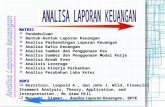KEUANGAN DAERAH
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of KEUANGAN DAERAH
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Indikasi keberhasilan otonomi daerah adalah adanya
peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin
baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan,
pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan
daerah serta antar daerah. Keadaan tersebut hanya akan tercapai
apabila daerah dapat mengelola pemerintahannya dengan diantaranya
adalah Administrasi Keuangan. Sistem pengelolaan Keuangan yang
baik akan memberikan manfaat pada efektivitas pelayanan public
dengan pemberian pelayanan yang tepat sasaran, meningkatkan mutu
pelayanan publik, biaya pelayanan yang murah karena hilangnya
inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan resources, alokasi
belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik, dan
meningkatkan public costs awareness sebagai akar pelaksanaan
pertanggung jawaban publik.
Pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi yang sekarang
ini dinikmati pemeirntah daerah Kabupaten dan Kota, memberikan
jalan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembaharuan dalam
sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah.
Kemunculan UU No. 22 dan 25 tahun 1999 telah melahirkan paradigma
baru dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Dalam
pengelolaan keuangan daerah, paradigma baru tersebut berupa
tuntutan untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang
berorientasi pada kepentingan publik (public oriented). Hal
tersebut meliputi tuntutan kepada pemerintah daerah untuk membuat
laporan keuangan dan transparansi informasi anggaran kepada
publik.
1.2. Perumusan Masalah
Belajar dari pengalaman internasional, pelaksanaan otonomi
daerah tidak selalu harus dibiayai oleh pendapatan yang berasal
dari daerah itu sendiri. Namun, secara pasti dapat dikatakan
bahwa apabila semakin maju industri suatu negara maka pelaksanaan
demokrasi akan semakin baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang
semakin demokratis akan tercermin dalam pelaksanaan otonomi
daerah yang semakin besar. Pelaksanaan otonomi yang semakin besar
tersebut dari aspek keuangan tercermin dari expenditure ratio
yang cenderung semakin besar. Dengan demikian, keberhasilan
pelaksanaan otonomi daerah dalam suatu negara tidak selalu harus
diukur dari besarnya peranan PAD untuk membiayai seluruh
aktivitas pemerintahan daerah.
Sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal, kebijakan
di bidang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) juga perlu
diatur dengan Undang-undang sesuai dengan amanat UUD 1945. Untuk
menghindari high cost economy, telah diterbitkan UU Nomor 18
Tahun 1997 tentang PDRD, kemudian sejalan dengan pelaksanaan
otonomi daerah, telah direvisi dengan UU Nomor 34 Tahun 2000
tentag PDRD. Prinsip-prinsip yang dianut dalam UU 34/2000 bukan
berarti dimaksudkan untuk menghambat pelaksanaan otonomi daerah
tetapi implementasi sistem perpajakan dan retribusi yang baik dan
bersifat universal.
Sesuai dengan UU 25/1999, perimbangan Keuangan antara Pusat
dan Daerah dilakukan melalui Dana Perimbangan (DP) yang terdiri
dari:
a) Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak
Penghasilan (PPh) Perseorangan, dan Sumber Daya Alam (SDA);
b) Dana Alokasi Umum (DAU);
c) Dana Alokasi Khusus(DAK).
Pelaksanaan otonomi Daerah secara efektif telah dimulai
sejak Januari 2001. Dari sisi keuangan negara hal tersebut telah
membawa konsekuensi kepada perubahan peta pengelolaan fiskal yang
cukup mendasar. Sebagaimana diketahui dalam APBN tahun 2001,
total dana yang didaerahkan melalui Dana Perimbangan (DP) adalah
sebesar Rp81,67 triliun.
Pembayaran tunggakan pinjaman Pemda dan BUMD pada dasarnya
merupakan kewajiban daerah sebagai pihak yang memperoleh manfaat
dari pinjaman tersebut.
1.3. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah :
1. Menjelaskan pengertian administrasi keuangan daerah, hubungan
keuangan daerah dengan keuangan pusat, serta pengurusan keuangan
daerah
2. Menjelaskan pengertian APBD, fungsi dan prinsip anggaran
daerah, struktur APBD, sumber-sumber penerimaan daerah, belanja
daerah, serta pembiayaan daerah
3. Memahami siklus anggaran, khususnya proses penyusunan APBD,
mulai dari penyusunan rancangan hingga penetapan APBD
4. Memahami proses pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban APBD
5. Menjelaskan pengertian penggantian kerugian daerah.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Pengertian Keuangan Daerah
Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam
penjelasan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :
“Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai
dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik
daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.
Menurut UU No. 17 tahun 2003 Keuangan Daerah/Negara adalah
semua dan kewajiban Daerah/Negara yang dapat dinilai dengan uang,
serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang
dapay dijadikan milik negara/daerah berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Adapun ruang lingkup keuangan daerah meliputi:
1. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah
serta melakukan pinjaman;
2. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan
daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. penerimaan daerah;
4. pengeluaran daerah;
5. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain
berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain
yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan
pada perusahaan daerah; dan
6. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam
penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan
umum. Rangka
2.1.1. Sistem Informasi Keuangan Daerah
Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah suatu
fasilitas yang diselenggarakan oleh Menteri Keuangan untuk
mengumpulkan, melakukan validasi, mengolah, menganalisis data,
dan menyediakan informasi keuangan daerah dalam rangka merumuskan
kebijakan dalam pembagian dana perimbangan, evaluasi kinerja
keuangan daerah, penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (RAPBN) serta memenuhi kebutuhan lain, seperti
statistik keuangan negara.
SIKD ini diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Sumber
informasi bagi sistem informasi keuangan daerah terutama adalah
laporan informasi APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
(1) UU Nomor 25 Tahun 1999, yaitu: informasi mengenai pengelolaan
keuangan daerah dan informasi mengenai kinerja keuangan daerah
dari segi efisiensi dan efektivitas keuangan dalam rangka
desentralisasi.
Tujuan penyelenggaraan SIKD adalah:
a. membantu Menteri Keuangan dalam merumuskan kebijakan keuangan
daerah;
b. membantu menyediakan data dan informasi kepada Sekretariat
Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (PKPD) pacla Dewan
Pertimbangan Otonomi Daerah;
c. membantu Menteri Keuangan dan instansi terkait IainnYa dalam
melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah, penyusunan RAPBN, dan
kebutuhan lain seperti statistik keuangan negara;
d. membantu pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakar keuangan
dan menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dar Belanja Daerah
(RAPBD), pemerintahan, dan pembangunan di Daerah.
2.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat
APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun
2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). Semua Penerimaan
Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam
APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam
rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi.
Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan
pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat
dalam APBD. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah
dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan
semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka
pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu.
Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi
target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua
pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran
yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar
pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi
kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan
daerah.
2.2.1. Fungsi-Fungsi Anggaran Daerah
Berbagai fungsi APBN/APBD sesuai dengan ketentuan dalam
Pasal 3 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
yaitu :
1. Fungsi Otorisasi
Anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan
belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi Perencanaan
Anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam
merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi Pengawasan
Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan
penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang
telah ditetapkan.
4. Fungsi Alokasi
Anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan
pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan
efektivitas perekonomian.
5. Fungsi Distribusi
Anggaran daerah harus mengandung arti/ memperhatikan rasa
keadilan dan kepatutan
6. Fungsi Stabilisasi
Anggaran daerah harus mengandung arti/ harus menjadi alat untuk
memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental
perekonomian.
2.2.2. Prinsip-Prinsip Anggaran Daerah
Prinsip-prinsip dasar (azas) yang berlaku di bidang
pengelolaan Anggaran Daerah yang berlaku juga dalam pengelolaan
Anggaran Negara / Daerah sebagaimana bunyi penjelasan dalam
Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
yaitu :
1. Kesatuan
Azas ini menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja
Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran.
2. Universalitas
Azas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan
secara utuh dalam dokumen anggaran.
3. Tahunan
Azas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun
tertentu
4. Spesialitas
Azas ini mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci
secara jelas peruntukannya.
5. Akrual
Azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani untuk
pengeluaran yang seharusnya dibayar, atau menguntungkan anggaran
untuk penerimaan yang seharusnya diterima, walaupun sebenarnya
belum dibayar atau belum diterima pada kas
6. Kas
Azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani pada
saat terjadi pengeluaran/ penerimaan uang dari/ ke Kas Daerah
Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan
belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka
13, 14, 15 dan 16 dalam UU Nomor 17 Tahun 2003, dilaksanakan
selambatlambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan
pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum
dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.
2.2.3 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:
1. Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui
Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang
merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu
dibayar kembali oleh Daerah.
Pendapatan daerah terdiri atas:
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b. Dana Perimbangan; dan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Pendapatan daerah, selain PAD dan Dana Perimbangan, adalah
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang meliputi hibah, dana
darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan oleh
pemerintah. Hibah yang merupakan bagian dari Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau
jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha
dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat.
2. Belanja Daerah
Komponen berikutnya dari APBD adalah Belanja Daerah. Belanja
daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah
yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban
daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh Daerah. Belanja daerah dipergunakan
dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan
wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan
perundang-undangan.
Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi,
program dan kegiatan, serta jenis belanja. Klasifikasi belanja
menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi
pemerintahan daerah.
2.3. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa
1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai
dengan tanggal 31 Desember. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
Dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah
melaksanakan kegiatan keuangan dalam siklus pengelolaan anggaran.
Pada dasarnya, siklus anggaran terdiri atas empat tahap,
yaitu:
1. Tahap persiapan dan penyusunan anggaran;
2. Tahap ratifikasi;
3. Tahap implementasi; dan
4. Tahap pelaporan dan evaluasi.
2.3.1. Tahap Persiapan dan Penyusunan Anggaran (Budget Preparation)
Pada tahap persiapan dan penysuunan anggaran dilakukan
taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang
tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu
diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran,
hendaknya terlebih dahulku dilakukan penaksiran pendapatan secara
lebih akurat. Selain itu, harus disadari adanya masalah yang
cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat
bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang anggaran
pengeluaran.
Dalam persoalan estimasi, yang perlu mendapat perhatian
adalah terdapatnya faktor “uncertainty” (tingkat ketidakpastian)
yang cukup tinggi. Oleh sebab itu manajer keuangan publik harus
memahami betul dalam menentukan besarnya suatu mata anggaran.
Besarnya suatu mata anggaran sangat tergantung pada teknik dan
sistem anggaran yang digunakan. Besarnya mata anggaran pada suatu
anggaran yang menggunakan “line-item budgeting”. Akan berbeda pada
“performance budgeting”, “input-output budgeting”, “program budgeting”, atau “zero
based budgeting”.
2.3.2. Tahap Ratifikasi Anggaran
Tahap berikutnya, adalah budget ratification. Tahap ini merupakan
tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup
berat. Pimpinan eksekutif (kepala daerah) dituntut tidak hanya
memiliki “managerial skill” namun juga harus mempunyai “political skill”,
“salesmanship”, dan “coalition building” yang memadai, integritas dan
kesiapan mental yang tinggi dan eksekutif sangat penting dalam
tahap ini. Hal tersebut penting karena dalam tahap ini pimpinan
eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan
argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan
bantahan-bantahan dari pihak legislatif.
2.3.3. Tahap Pelaksanaa Anggaran (Budget Implementation)
Setelah anggaran disetujui oleh legislatif, tahap berikutnya
adalah pelaksanaan anggaran. Dalam tahap ini, hal terpenting yang
harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah
dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian
manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggung
jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal
untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah
disepakati, dan bahkan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan
anggaran periode berikutnya. Sistem akuntansi yang digunakan
hendaknya juga mendukung pengendalian anggaran.
2.3.4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran
Tahap terakhir dari siklus anggaran asalah pelaporan dan
evaluasi anggaran. Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi
anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan
tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas.
Apabila pada tahap implementasi telah didukung dengan sistem
akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka pada
tahap pelaporan dan evaluasi anggaran biasanya tidak akan menemui
banyak masalah.
Penyusunan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah
Daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk
tercapainya tujuan bernegara. APBD, perubahan APBD, dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan setiap tahun
dengan peraturan daerah. Dalam menyusun APBD, penganggaran
pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian atas
tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Pendapatan,
belanja dan pembiayaan daerah Pada akhir pemelajaran ini peserta
dapat memahami siklus anggaran, khususnya proses penyusunan APBD,
mulai dari penyusunan rancangan hingga penetapan APBD.
Pemerintah Daerah perlu menyusun APBD untuk menjamin
kecukupan dana dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya.
Karena itu, perlu diperhatikan kesesuaian antara kewenangan
pemerintahan dan sumber pendanaannya. Pengaturan kesesuaian
kewenangan dengan pendanaannya adalah sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah didanai dari dan atas beban APBD.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
pemerintah pusat di daerah didanai dari dan atas beban APBN.
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi yang penugasannya
dilimpahkan kepada kabupaten/kota dan/atau desa, didanai dari dan
atas beban APBD provinsi.
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten/kota yang
penugasannya dilimpahkan kepada desa, didanai dari dan atas beban
APBD kabupaten/kota.
Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik
dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang
berkenaan harus dianggarkan dalam APBD. Penganggaran penerimaan
dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran.
Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan
kewajiban pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan.
2.4. Pelaksanaan, Penatausahaan APBD
2.4.1. Pelaksanaan APBD
Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD.
Pelaksanaan APBD meliputi pelaksanaan anggaran pendapatan,
belanja, dan pembiayaan. Penjelasan berikut ini didasarkan pada
Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.
Pengeluaran dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau
disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Kriteria keadaan
darurat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan Anggaran oleh Kepala SKPD dilaksanakan setelah
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) ditetapkan oleh PPKD
dengan persetujuan Sekretaris Daerah. Proses penetapan DPA-SKPD
adalah sebagai berikut. APBD ditetapkan, memberitahukan kepada
semua kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD.
Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima
pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau
penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan. Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung
untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh
peraturan perundang-undangan. Penerimaan SKPD berupa uang atau
cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1(satu)
hari kerja oleh Bendahara Penerimaan dengan didukung oleh bukti
yang lengkap.
Semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum
daerah. SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang
ditetapkan dalam peraturan daerah. SKPD yang mempunyai tugas
memungut dan/atau menerima dan/atau kegiatannya berdampak pada
penerimaan daerah wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan
tersebut.
Semua penerimaan daerah apabila berbentuk uang harus segera
disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi
milik/asset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah.
Pengembalian atas kelebihan pajak, retribusi, pengembalian
tuntutan ganti rugi dan sejenisnya dilakukan dengan membebankan
pada rekening penerimaan yang bersangkutan untuk pengembalian
penerimaan yang terjadi dalam tahun yang sama. Untuk pengembalian
kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya
dibebankan pada rekening belanja tidak terduga. Jumlah belanja
yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk
setiap pengeluaran belanja. Pengeluaran tidak dapat dibebankan
pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak
tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD. Setiap SKPD
dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk
tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD. Pengeluaran
belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif,
efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap
dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat
dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD
ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah. Pengeluaran kas
tersebut tidak termasuk belanja yang bersifat mengikat dan
belanja yang bersifat wajib.
Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan Surat
Penyediaan Dana (SPD), atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD
(DPA-SKPD), atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
Khusus untuk biaya pegawai diatur bahwa gaji pegawai negeri sipil
daerah dibebankan dalam APBD. Pemerintah daerah dapat memberikan
tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah
berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan
kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pengelolaan anggaran pembiayaan daerah dilakukan oleh
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Semua penerimaan dan
pengeluaraan pembiayaan daerah dilakukan melalui Rekening Kas
Umum Daerah.
Untuk pencairan dana cadangan, pemindahbukuan dari rekening
dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan
rencana pelaksanaan kegiatan, setelah jumlah dana cadangan yang
ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang pembentukan dana
cadangan yang berkenaan mencukupi. Pemindahbukuan tersebut paling
tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk
mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan
sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang
pembentukan dana cadangan. Pemindahbukuan dari rekening dana
cadangan ke rekening kas umum daerah tersebut dilakukan dengan
surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan
PPKD.
Penjualan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dilakukan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pencatatan penerimaan
atas penjualan kekayaan daerah didasarkan pada bukti penerimaan
yang sah. Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah
pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran yang
bersangkutan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian
pinjaman berkenaan. Penerimaan pinjaman dalam bentuk mata uang
asing dibukukan dalam nilai rupiah. Penerimaan kembali pemberian
pinjaman daerah didasarkan pada perjanjian pemberian pinjaman
daerah sebelumnya, untuk kesesuaian pengembalian pokok pinjaman
dan kewajiban lainnya yang menjadi tanggungan pihak peminjam.
Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan mencakup pelaksanaan
pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran pokok
utang, dan pemberian pinjaman daerah. Jumlah pendapatan daerah
yang disisihkan untuk pembentukan dana cadangan dalam tahun
anggaran bersangkutan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam
peraturan daerah. Pemindahbukuan jumlah pendapatan daerah yang
disisihkan yang ditransfer dari rekening kas umum daerah ke
rekening dana cadangan dilakukan dengan surat perintah
pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
2.4.2. Penatausahaan Keuangan Daerah
Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara
penerimaan, bendahara pengeluaran dan orang atau badan yang
menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib
menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada
bank pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUD
menerima nota kredit.
Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan
terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang
menjadi tanggung jawabnya. Bendahara penerimaan pada SKPD wajib
mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang
yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya. Disamping pertanggungjawaban secara administratif,
Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggung jawabkan
secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung
jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya.
2.5. Akuntansi Keuangan Daerah
Pelaksanaan otonomi daerah yang mendukung efisiensi
penggunaan keuangan negara dapat dilihat dari sisi pelaksanaan
fungsi pelayanan pemerintahan yang bersifat lokal. Sebelum
otonomi daerah dilaksanakan, fungsi pemerintahan yang bersifat
lokal (seperti pembangunan prasarana yang manfaatnya hanya
bersifat lokal) sering dikelola oleh instansi Pusat. Hal ini
sering memberikan dampak biaya yang relatif lebih besar daripada
apabila fungsi tersebut dilaksanakan oleh Pemda.
Konsep good governance di bidang dana perimbangan
sebagaimana diatur melalui PP Nomor 104 Tahun 2000 paling tidak
dapat dilihat dalam proses pengambilan keputusannya. Perumusan
alokasi dana perimbangan telah melibatkan pihak
universitas/pakar, kemudian sebelum ditetapkan dengan Keppres,
setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari DPOD yang
mayoritas anggotanya berasal dari Pemda. Kemudian selanjutnya
produk dari keputusan tersebut dapat diketahui semua lapisan
masyarakat.
Implementasi prinsip-prinsip good governance pengelolaan
keuangan daerah dalam kaitannya dengan kebijakan desentralisasi
fiskal telah diatur dalam PP 105/2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagai derivasi atau
penjelasan lebih lajut dari UU 25/1999. PP tersebut telah
mengatur secara tegas mengenai pengelolaan keuangan daerah, yaitu
:
• Pengaturan : Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah, sedangkan mengenai sistem dan
prosedurnya (penatausahaan) diatur dengan peraturan kepala
daerah;
• Perencanaan : Penganggaran berdasarkan pendekatan kinerja. Ke
depan penganggaran harus diarahkan pada unified budget, sehingga
tidak akan ada lagi dikhotomi antara anggaran rutin dan
pembangunan yang selama ini sering tumpang tindih.
• Pelaksanaan : Penatausahaan berdasarkan standar akuntansi
keuangan pemerintah daerah yang berlaku. Selama ini, pencatatan
keuangan daerah bersifat pembukuan tunggal (single entry) dan
berbasis kas (cash basis). Ke depan akan di arahkan pada
pembukuan berpasangan (double entry) dan secara bertahap akan
mengarah pada basis akrual (acrual basis).
• Pertanggungjawaban : Pertanggungjawaban keuangan kepala daerah
terdiri dari Perhitungan APBD, Nota Perhitungan APBD, Laporan
Aliran Kas, dan Neraca.
Selanjutnya PP 11/2001 tentang Informasi Keuangan Daerah
yang merupakan produk hukum lain yang diamanatkan oleh UU
25/1999, menyatakan perlunya suatu sistem informasi keuangan
daerah. Sebagai dokumen publik informasi tentang keuangan daerah
dapat diketahui oleh masyarakat secara terbuka. Untuk memudahkan
masyarakat mendapatkan informasi mengenai penggunaan dana yang
diperoleh dari masyarakat melalui pajak dan retribusi, perlu
adanya suatu sistem informasi keuangan daerah (SIKD). Melalui
SIKD, informasi tidak lagi ditujukan hanya untuk konsumsi lokal
dan nasional, tetapi sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan
internasional sebagaimana dijabarkan dalam Government Financial
Statistics (GFS) yang dikeluarkan oleh International Monetary
Fund (IMF) dimana Indonesia juga sebagai salah satu anggota
Untuk melakukan penyusunan laporan keuangan, Pemerintah
daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah yang mengacu
kepada standar akuntansi pemerintahan. Sistem akuntansi
pemerintah daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah (SKPKD) sebagai entitas pelaporan dan Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi.
Sistem akuntansi pemerintahan daerah meliputi serangkaian
prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara
manual atau menggunakan aplikasi komputer. Proses tersebut
didokumentasikan dalam bentuk buku jurnal dan buku besar, dan
apabila diperlukan ditambah dengan buku besar pembantu.
Sistem akuntansi pemerintahan daerah sekurang-kurangnya
meliputi:
1. prosedur akuntansi penerimaan kas;
2. prosedur akuntansi pengeluaran kas;
3. prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah; dan
4. prosedur akuntansi selain kas.
Sistem akuntansi pemerintahan daerah disusun dengan
berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai dengan
peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengendalian internal
dan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan.
Sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh PPKD.
Sistem akuntansi SKPD dilaksanakan oleh PPKSKPD. PPK-SKPD
mengkoordinasikan pelaksanaan sistem dan prosedur penatausahaan
bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas
pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi:
1. laporan realisasi anggaran;
2. neraca;
3. laporan arus kas; dan
4. catatan atas laporan keuangan.
Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas
akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi:
1. laporan realisasi anggaran;
2. neraca; dan
3. catatan atas laporan keuangan.
2.6. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif,
transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas
keadilan dan kepatutan. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan
daerah dalam tahun anggaran tertentu. Ketentuan ini berarti,
bahwa APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah
dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
dalam tahun anggaran tertentu. Dengan demikian, pemungutan semua
penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Semua
pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran
yang ditetapkan dalam APBD, sehingga APBD menjadi dasar bagi
kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan
daerah.
Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka
desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD. Semua penerimaan
daerah dan pengeluaran daerah yang tidak berkaitan dengan
pelaksanaan dekosentrasi atau tugas pembantuan merupakan
penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi. APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD
ditetapkan dengan peraturan daerah dan merupakan dokumen daerah.
2.7. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Ketentuan mengenai penyelesaian maupun pengenaan ganti
kerugian negara/daerah diatur dalam Bab IX Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, Bab XI Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta dalam Bab V
Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
2.7.1. Penyelesaian Kerugian Daerah
Penyelesaian kerugian daerah adalah sebagai berikut :
a. Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan
melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera
diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
b. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain
yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan
kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan
negara, wajib menggantikan kerugian tersebut.
c. Setiap pimpinan kementrian negara/lembaga/kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dapat segera melakukan tuntutan ganti
rugi setelah mengetahui bahwa dalam kementrian
negara/lembaga/SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat
perbuatan dari pihak manapun.
d. Setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung
atau oleh kepala SKPD kepada gubernur/bupati/walikota dan
diberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja
setelah kerugian daerah itu diketahui.
e. Segera setelah kerugian daerah diketahui, kepada bendahara,
pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyatanyata
melanggar hukum dapat segera dimintakan surat pernyataan
kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi
tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah
dimaksud.
f. Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM) tidak
mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian
daerah, maka gubernur/bupati/walikota yang bersangkutan segera
mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian
sementara kepada yang bersangkutan.
g. Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan
oleh BPK. Apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah ditemukan
unsur pidana, maka BPK menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
h. Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri
bukan bendahara, atau pejabat lain ditetapkan oleh
menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota. Tatacara
tuntutan ganti kerugian negara/daerah diatur dengan peraturan
pemerintah.
i. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain
yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah
dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
j. Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi.
2.7.2. Pengenaan Ganti Kerugian Negara/Daerah
Tatacara tuntutan ganti kerugian negara/daerah maupun
pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri
bukan bendahara, atau pejabat lain diatur dengan peraturan
pemerintah yang merupakan petunjuk pelaksanaan ketiga paket
undang-undang di atas. Ketentuan tersebut diharapkan dapat
digunakan oleh pihakpihak yang terkait dalam menangani dan
menyelesaikan kerugian negara/daerah yang semakin hari semakin
bertambah besar, sehingga dapat diantisipasi terjadinya kerugian
daerah, dicegah penyelesaian kerugian daerah yang berlarut-
larut, serta dipercepat proses pemulihan kerugian daerah maupun
diperkecil terjadinya kerugian daerah.
2.8. Tata Cara Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah
Penyelesaian kerugian keuangan daerah melalui upaya damai
dilakukan apabila penggantian kerugian keuangan daerah dilakukan
secara tunai sekaligus dan angsuran dalam jangka waktu
selambatlambatnya 2 (dua) tahun dengan menandatangani Surat
Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTJM).
Penyelesaian kerugian keuangan daerah melalui proses
Tuntutan Perbendaharaan dilakukan apabila upaya damai yang
dilakukan secara tunai sekaligus atau angsuran tidak berhasil.
Proses penuntutannya merupakan kewenangan kepala daerah melalui
Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti
Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Majelis Pertimbangan). Apabila
pembebanan perbendaharaan telah diterbitkan, kepala daerah
melakukan eksekusi keputusan dimaksud dan membantu proses
pelaksanaan penyelesaiannya.
Penyelesaian kerugian keuangan daerah melalui proses
Tuntutan Ganti Rugi dilakukan apabila upaya damai yang dilakukan
secara tunai sekaligus atau angsuran tidak berhasil.
BAB III
KESIMPULAN
Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai
dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan
Daerah kemudian adalah seluruh kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
Pengelolaan Administrasi Keuangan daerah merupakan salah
satu perhatian utama para pengambil keputusan di pemerintahan,
baik di tingkat pusat maupun daerah. Sejalan dengan hal tersebut,
berbagai perundang-undangan dan produk hukum telah ditetapkan dan
mengalami perbaikan atau penyempurnaan untuk menciptakan sistem
pengelolaan anggaran yang mampu memenuhi berbagai tuntutan dan
kebutuhan masyarakat, yaitu terbentuknya semangat desentralisasi,
demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses
penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan
keuangan daerah.
Secara garis besar, pengelolaan keuangan daerah dapat dibagi
menjadi dua bagian, yaitu manajemen penerimaan daerah dan
manajemen pengeluaran daerah. Kedua komponen tersebut akan sangat
menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka
melaksanakan otonomi daerah.
REFERENSI
A. Buku
1. Ahmad Yani, S.H., M.M., Ak., Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Daerah di Indonesia, Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT Raja
Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan kedua, April, 2004.
2. Anwar Sulaiman H., Drs., Manajemen Aset Daerah, STIA-LAN, 2000
3. Arifin P. Soeria Atmadja, Dr., Mekanisme Pertanggungjawaban
Keuangan Negara, PT Gramedia, Jakarta, 1986.
4. Badan Pemeriksa Keuangan, Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan
dan Tuntutan Ganti Rugi, 1976.
5. BPKP, Pedoman Penanganan Penggantian Kerugian Negara, 1993.
6. Darise, Nurlan, Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta, Penerbit PT
Indeks, 2006.
7. __________, Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD), Jakarta, Penerbit PT Indeks, 2007.
8. Devas, Nick, et al., Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, Jakarta,
Penerbit Universitas Indonesia, 1989.
9. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H., Determinasi Kebijakan Anggaran
Negara Indonesia, Studi Yuridis, Papas Sinar Sinanti, Jakarta 2005.
10. Gade, Muhammad. 1998. Akuntansi Pemerintahan. Edisi Revisi.
Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
11. Goedhart C., Dr., Garis-Garis Besar Ilmu Keuangan Negara, Terjemahan
oleh Ratmoko, S.H., Penerbit Jembatan, Jakarta, 1981.
12. Hadi, M., Administrasi Keuangan RI, Jakarta, 1981.
13. Halim, Abdul (editor), Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah,
Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2001.
14. Halim, Abdul, Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta,
Penerbit Salemba Empat, 2002.
15. Kansil CST, Prof. Drs., S.H.dan Kansil Christine S.T., S.H.,
M.H. 2001. Kitab Undang-Undang Otonomi Daerah 1999 – 2001; Kitab 2.
Jakarta: PT Pradnya Paramita.
16. Mardiasmo, Prof., Dr., MBA., Ak., Akuntansi Sektor Publik, Penerbit
ANDI Yogyakarta, 2004.
17. Modul Sistem Administrasi Keuangan Daerah II , Edisi Keempat,
2004.
18. Modul-Modul Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
19. Pendapatan Nasional. Edisi ke-5. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
20. Rasul Sjahrudin, Dr., SH., Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas
Kinerja dan Anggaran Dalam Perspektif UU No. 17 Tahun 2003, PNRI,
Jakarta 2003.
21. Sugijanto, Drs., Ak., dkk., Akuntansi Pemerintahan dan Organisasi Non
Laba, Pusat Pengembagan Akuntansi FE-UI, Jakarta, 1995.
B. Perundang-Undangan
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1997 tentang
Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan Keuangan dan
Barang Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2005 tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Negara/Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan.
5. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan
Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
8. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah.
9. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
11. Undang-Undang No. 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak.
12. Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa.
13. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
14. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
C. Internet
1. www.pusdiklatwas.bpkp.go.id
2. www.depdagri.go.id