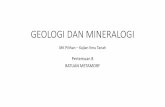GEOLOGI DAN POTENSI BATUAN TUFA SEBAGAI BAHAN ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of GEOLOGI DAN POTENSI BATUAN TUFA SEBAGAI BAHAN ...
Program Studi Teknik Geologi, Fakultas Teknik – Universitas Pakuan 1
GEOLOGI DAN POTENSI BATUAN TUFA SEBAGAI BAHAN BAKU
INDUSTRI DAERAH KARANGMEKAR DAN SEKITARNYA
KECAMATAN KARANGNUNGGAL KABUPATEN TASIKMALAYA,
PROVINSI JAWA BARAT
Bei Hasbiana Azizah1), Djauhari Noor2), dan Iwan Ridwansyah3)
ABSTRAK
Tujuan penelitian dan pemetaan geologi Daerah Karangmekar dan sekitarnya, Kecamatan Karangnunggal,
Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat adalah untuk mengetahui tatanan geologi yang mencakup
Geomorfologi, Stratigrafi, Struktur Geologi, Sejarah Geologi dan Perhitungan Sumberdaya Tufa Formasi
Bentang di daerah penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi
pustaka, penelitian lapangan, analisa laboratorium dan studio yang keseluruhan dituangkan dalam sebuah
laporan tugas akhir. Hasil yang dicapai dalam penelitian dan pemetaan geologi daerah Daerah
Karangmekar dan sekitarnya, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat adalah
sebagai berikut: Geomorfologi daerah penelitian berdasarkan morfogenesanya dapat dibagi menjadi 2
(dua) satuan geomorfologi, yaitu (1). Satuan geomorfologi perbukitan lipatan sub satuan geomorfologi
perbukitan homoklin yang berstadia dewasa; (2). Satuan geomorfologi dataran aluvial yang berstadia
muda. Pola aliran sungai yang terdapat di daerah penelitian berpola rectangular dengan stadia erosi
sungainya berada pada tahapan muda dan dewasa. Tatanan batuan yang terdapat di daerah penelitian dari
tua ke muda adalah sebagai berikut: Satuan batuan tufa dan lava (Formasi Jampang) dengan umur Miosen
Awal dan diendapkan di darat; Satuan batuan batugamping pasiran (Formasi Kalipucang) dengan umur N9-
N13 atau Miosen Tengah dan diendapkan pada kedalaman 20-100 meter atau pada zona neritik tengah;
Satuan batuan batupasir, batugamping dan tufa (Formasi Bentang) dengan umur N16-N19 atau Miosen
Akhir Bagian Tengah - Awal Pliosen dan diendapkan pada kedalaman 30-91 meter atau pada zona neritik
tengah; Satuan endapan aluvial sungai berumur Holosen dan diendapkan diatas batuan- batuan yang lebih
tua dan dibatasi oleh bidang erosi. Struktur geologi yang dijumpai di daerah penelitian terdiri dari struktur
kekar, lipatan dan sesar. Struktur kekar berupa kekar gerus sedangkan struktur lipatan berupa lipatan
homoklin dan struktur sesar berupa sesar mendatar Cinunjang dan sesar mendatar Cikalapa. Keseluruhan
struktur yang terdapat di daerah penelitian terjadi dalam satu periode tektonik, yaitu pada kala Pliosen
Akhir - Plistosen dengan arah gaya N 155o E atau relative baratlaut-tenggara. Hasil perhitungan cadangan
sumberdaya batuan tufa dengan metode konturing dengan sumberdaya tingkat spekulatif dan hipotesis
diperoleh total cadangan tufa sebesar 52.198.632,5 Ton. Berdasarkan hasil analisa kimiawi menggunakan
metode ICP (Inductivetively Coupled Plasma) dan diagram avgustinik maka sumberdaya tufa daerah
penelitian dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku bata klinker dan bata biasa.
Kata Kunci : Geologi, Geomorfologi, Stratigrafi, Struktur Geologi, Sumberdaya Tufa
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Latar belakang penelitian dan pemetaan
geologi di daerah Karangmekar, Kecamatan
Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya,
Provinsi Jawa Barat dilakukan berdasarkan pada
alasan-alasan sebagai berikut:
1. Daerah penelitian secara fisiografi berada pada
Zona Pegunungan Selatan Jawa Barat (Van
Bemmelen, 1949) dan zona ini secara tektonik
merupakan busur gunungapi yang terbentuk
dari hasil tumbukan lempeng (subduksi) dari
lempeng India-Australia dengan lempeng
Eurasia (Katili, J.A., 1975).
2. Berdasarkan data peta geologi Lembar
Karangnunggal, Jawa Barat yang dibuat oleh
Supriatna, S., dkk., (1992), sejarah
sedimentasi di daerah ini dimulai dengan
terbentuknya busur gunungapi hasil tumbukan
lempeng India-Australia dengan lempeng
Eurasia pada kala Oligosen Akhir hingga
Awal Miosen yang kemudian materialnya
diendapkan sebagai Formasi Jampang dan
Anggota Genteng. Kemudian pada Akhir
Miosen Awal - awal Miosen Tengah daerah ini
mengalami orogenesa (tektonik) yang
menjadikan daerah ini menjadi laut dangkal
dan mulai diendapkan batuan-batuan Formasi
Pamutuan dan Formasi Kalipucang. Pada kala
Miosen Atas mulai diendapkan batuan
Formasi Bentang. Pada Pliosen daerah ini
mengalami orogenesa kembali disertai dengan
aktivitas volkanisme yang hasilnya
diendapkan sebagai endapan gunungapi. Sejak
kala Pleistosen - Holosen daerah ini telah
Program Studi Teknik Geologi, Fakultas Teknik – Universitas Pakuan 2
berupa daratan sehingga proses- proses
eksogenik bekerja pada batuan-batuan yang
tua dan hasilnya diendapkan sebagai endapan
permukaan dan endapan aluvial.
3. Ditinjau dari pola struktur geologinya, Lembar
Karangnunggal memiliki pola struktur yang
berarah baratdaya - timurlaut sedangkan pola
struktur di Pulau Jawa menurut Soejono
Martodjojo dan Pulunggono (1994), diketahui
bahwa pola struktur pulau Jawa pada kala
Oligosen Akhir - Pleistosen berarah barat -
timur.
Berdasarkan kondisi fisiografi, sejarah
sedimentasi dan pola struktur geologi yang
berpengaruh selama zaman Tersier, maka
penulis tertarik melakukan penelitian dan
pemetaan geologi di daerah Karangmekar dan
sekitarnya, Kecamatan Karangnunggal,
Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat.
1.2. Maksud dan Tujuan
Penelitian geologi daerah Karangmekar dan
sekitarnya, Kecamatan Karangnunggal,
Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat
dimaksudkan untuk memenuhi salah satu
persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan
sarjana strata satu (S-1) pada Program Studi
Teknik Geologi, Fakultas Teknik, Universitas
Pakuan.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui tatanan geologi di daerah
Karangmekar dan sekitarnya, Kecamatan
Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya,
Provinsi Jawa Barat yang meliputi geomorfologi,
stratigrafi,struktur geologi dan sejarah geologi
serta mengevaluasi potensi sumberdaya bahan
galian tufa Formasi Pamutuan yang terdapat di
daerah penelitian.
1.3. Letak, Luas dan Kesampaian Daerah
Penelitian
Secara administrasi daerah penelitian berada
di wilayah Kecamatan Karangnunggal,
Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat.
Secara geografis daerah penelitian terletak
pada 108° 11' 00" - 108° 14' 10" BujurTimur dan
7° 36' 00"
- 7° 39' 30" Lintang Selatan dan berada pada Peta
Rupabumi Digital Indonesia Lembar
Karangnunggal No.1308-132; Lembar Cibalong
No. 1308-134, skala 1:25.000 yang diterbitkan
oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan
Nasional (Bakosurtanal), Edisi-1, Tahun 1999.
Luas daerah penelitian adalah 7 km x 7 km atau 49 km2 yang berada dalam Peta Geologi
Lembar Karang nunggal, Jawa, skala 1:100.000 dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi (P3G), Bandung.
Daerah penelitian dapat dicapai dari Bogor
menggunakan Bus antar provinsi. Dengan rute
Bogor- Jakarta, lalu dilanjutkan dengan rute
Jakarta- Tasikmalaya, dengan jarak ±317 km dan
waktu tempuh sekitar 7 jam. Dari kota
Tasikmalaya dilanjutkan menuju Karangnunggal
dengan menggunakan bus antar kabupaten
dengan rute Tasikmalaya-Karangnunggal yang
berjarak sekitar 44 km dengan waktu tempuh
sekitar jam perjalanan.
Gambar 1.1. Letak Geografis Daerah
Penelitian Sumber : Peta Rupa Bumi Lembar Cibalong
1.4. Metodologi Penelitian
Metode penelitian dan pemetaan geologi
yang dipakai dalam penelitian ini melalui
beberapa tahapan sebagai berikut: (1). Tahap
Persiapan (Studi Pustaka, Persiapan Lapangan
dan Penyusunan Proposal); (2). Tahap Pekerjaan
Lapangan (Tahap Pengambilann Data
Lapangan); (3). Tahap Analisis Laboratorium
dan Studio; (4). Tahap Penyusunan Laporan
Akhir.
1.5. Kajian Pustaka
Sebagai bahan acuan dalam melakukan
penelitian geologi ini, penulis mempelajari hasil
laporan hasil peneliti terdahulu baik yang
bersifat lokal maupun regional. Peneliti-peneliti
tersebut, antara lain:
1. Bemmelen, R. W. Van, (1949), The Geology
of Indonesia, Volume IA : General Geology
of Indonesia and Adjacent Archipelagoes,
Government Printing Office, The Hague, 732
p.
2. Supriatna, S., dkk., (1992), Peta Geologi
Lembar Karangnunggal, Jawa Skala
1:100.000 yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi (P3G), Bandung.
3. Soejono Martodjojo dan Pulunggono, A.,
1994, Geotektonik Pulau Jawa Sejak Akhir
Mesozoik Hingga Kuarter, Makalah Seminar
Geologi, Jurusan Teknik, Universitas Gajah
Program Studi Teknik Geologi, Fakultas Teknik – Universitas Pakuan 3
Mada, Yogyakarta.
II. GEOLOGI UMUM
2.1. Geomorfologi
2.1.1. Fisiografi Jawa Barat
Menurut van Bemmelen (1949), Pulau Jawa
bagian barat dibagi menjadi 5 zona fisiografi,
yaitu: 1. Zona Dataran Pantai Jakarta. 2. Zona Bogor. 3. Zona Bandung dan Pegunungan Bayah
pada Zona Bandung.
4. Zona Pegunungan Selatan Jawa Barat.
5. Gunungapi Kuarter.
Gambar 2.1. Fisiografi Jawa Barat (Van Bemmelen, 1949)
Sumber : The Geology of Indonesia
Berdasarkan pembagian zona fisiografi Van
Bemmelen (1949) dengan memperhatikan
bentuk- bentuk bentangalam dan batuan-batuan
yang menyusun bentangalam yang ada di daerah
penelitian, dimana di daerah penelitian memiliki
ekspresi topografi berupa perbukitan
bergelombang landau hingga terjal yang tersusun
oleh batuan-batuan sedimen yang terlipat dan
terpatahkan, maka morfologi daerah penelitian
dapat dimasukan ke dalam Zona Pegunungan
Selatan.
2.1.2. Geomorfologi Daerah Penelitian
Berdasarkan genetika pembentukan
bentang alamnya, serta merujuk pada struktur,
proses dan stadia (tahapan) geomorfiknya maka
geomorfologi daerah penelitian dibagi menjadi
dua satuan, yaitu:
1. Satuan Geomorfolgi Perbukitan Lipatan
Sub Satuan Geomorfologi Perbukitan
Homoklin 2. Satuan Geomorfolgi Dataran Aluvial
Gambar 2.2. Peta Geomorfologi Daerah Penelitian
1. Satuan Geomorfolgi Perbukitan Lipatan
Sub Satuan Geomorfologi Perbukitan
Homoklin
Penyebaran satuan ini menempati 96% dari
luas daerah penelitian. Satuan geomorfologi
perbukitan sub homoklin yang terdapat pada
daerah penelitian di kontrol oleh struktur
perlipatan yang menghasilkan bentuk perbukitan
yang memiliki arah perlapisan relatif barat - timur
dengan kemiringan lapisan ke arah selatan. Satuan
ini ditempati oleh satuan batuan tufa dan lava,
satuan batuan batugamping, dan satuan batuan
batupasir, batugamping dan tufa. Morfometri
satuan ini berada pada ketinggian 112-450mdpl
dengan kemiring an lereng lereng 6°- 55°.
Hasil dari proses-proses eksogenik
(pelapukan, erosi/ denudasi, dan sedimentasi)
yang teramati pada satuan geomorfologi ini
adalah tanah sebagai hasil dari pelapukan batuan
dengan ketebalan tanah berkisar 1-3 meter. Hasil
proses erosi/denudasi menghasilkan bentuk
bentangalam alur-alur hingga bentuk lembah.
Hasil pelapukan batuan dan hasil erosi/denudasi
umumnya diendapkan pada topografi berelief
ladai-datar sebagai endapan permukaan dan
sebagian lagi masuk kedalam sistem sungai yang
terdapat di daerah penelitian dan diendapkan
sebagai endapan alluvial sungai.
Jentera geomorfik satuan geomorfologi ini
berada dalam tahap dewasa yang didasarkan
pada hasil proses eksogenik pada bentangalam
satuan geomorfologi ini telah berubah
menghasilkan bentuk-bentuk morfologi alur dan
morfologi lembah dengan relief topografi
bertekstur kasar.
2. Satuan Geomorfolgi Dataran Aluvial
Satuan geomorfologi dataran aluvial di
daerah penelitian terletak di bagian selatan
lembar peta menempati 4% dari luas daerah
penelitian dan tersebar di sepanjang Sungai
Cikalapa. Pada peta geomorfologi satuan
geomorfologi ini diberi warna biru muda.
Genetika satuan geomorfologi ini terbentuk
dari hasil pengendapan material lepas berukuran
lempung hingga bongkah yang diangkut air
sungai. Secara morfometri satuan ini berada pada
ketinggian 87,5-112 mdpl, dengan kemiringan
lereng lereng 0°- 5°.
Proses geomorfologi yang teramati berupa
erosi dan sedimentasi batuan yang berasal dari
hulu sungai yang kemudian tertransportasikan
dan terendapkan di daerah sekitar sungai dengan
energi yang rendah, sehingga terbentuk bentukan
morfologi khas endapan aluvial ini seperti
Program Studi Teknik Geologi, Fakultas Teknik – Universitas Pakuan 4
dataran banjir dan gosong pasir.
Jentera geomorfik satuan geomorfologi ini
termasuk dalam stadia geomorfik muda
dikarenakan proses sedimentasi masih
berlangsung hingga saat ini.
2.1.3. Pola Aliran Sungai
Secara umum pola aliran sungai daerah penelitian
adalah pola aliran rectangular yaitu pola aliran
yang dibentuk oleh cabang-cabang sungai yang
dikendalikan oleh struktur geologi, seperti kekar
(rekahan) dan sesar (patahan). Sungai rektangular
dicirikan oleh saluran-saluran air yang mengikuti
pola dari struktur kekar dan patahan.
2.2 Stratigrafi
2.2.1. Stratigrafi Lembar Karangnunggal
Berdasarkan peta geologi lembar
Karangnunggal skala 1:100.000 oleh Supriatna
S. dkk (1992), tatanan batuan dari yang tertua
hingga termuda adalah sebagai berikut (table
1.1.):
Tabel 1. Kolom Stratigrafi Karangnunggal
Sumber : Peta Geologi Lembar Karangnunggal
1. Formasi Jampang
Terdiri atas breksi aneka bahan dan tuf
bersisipan lava. Sebarannya terutama di bagian
tengah dan timur laut Lembar dan sedikit bagian
barat daya; umurnya diperkirakan Oligosen-
Miosen; tebal satuan sekitar 900 m.
2. Anggota Genteng Formasi Jampang
Terdiri dari Tuf berselingan dengan breksi
dasitan, bersisipan batugamping. Satuan ini
mengandung mineral-mineral hitam (mineral
bijih) dan kuarsa sebagai mineral pencampur.
Dalam batugamping Formasi Jampang
ditemukan pula kandungan foraminifera plangton
yang menunjukan umur Miosen
Bawah-Miosen Tengah (N8-N9). Lingkungan pengen- dapannya adalah laut dalam dan terbuka, kemungkinan pada cekungan rumpang parit
busur. Sebarannya di bagian selatan dan badatdaya Lembar. Tebalnya diperkirakan 900 m.
3. Formasi Pamutuan
Terdiri dari batupasir, batugamping, napal,
batulempung dan tuf. Fosil dijumpai dalam napal
dan batugamping dari jenis foraminifera, antara
lain Globocassidulina sp., Amphistegina sp.,
Globoquadrina altispira sp., (CUSHMAN AND
JARVIS), Globo- rotalia mayeri (CUSHMAN
AND ELLISOR) dan Gyroidina sp., kumpulan
fosil tersebut menunjukan umur Miosen Tengah
dengan lingkungan pengendapatn laut dangkal
dan agak terbuka.
Formasi Pamutuan diduga menindih selaras
Formasi Jampang, dan diduga menjemari dengan
Formasi Kalipucang serta tertindih tak selaras
oleh Formasi Bentang. Sebarannya terdapat di
bagian timur Lembar dan meluas ke arah timur
pada Lembar Pangandaran. Singkapan yang baik
terdapat di daerah aliran sungai Pamutuan (di
Lembar Pangandaran). Tebal formasi ini
diperkirakan antara 300 m dan 600 m.
4. Anggota Tuf Napalan Formasi Pamutuan
Terdiri dari tuf napalan berselingan dengan
batupasir tufan dan batulempung tufan. Umur
satuan dikorelasikan dengan batuan yang sama di
Lembar Pangandaran yang mengandung fosil
foraminifera kecil yang menunjukan umur
Miosen Tengah, lingkungan pengendapannya
laut dangkal dan terbuka. Satuan ini hanya
terdapat di bagian timur Lembar. Tebal satuan
diperkirakan antara 200 m hingga 500 m. Satuan
ini menjemari dengan Anggota Batugamping
Formasi Pamutuan.
5. Anggota Batugamping Formasi Pamutuan
Terdiri dari batugamping pasiran, kalsilutit
dan napal. Napal ini dapat dikorelasikan dengan
napal yang sama dari Anggota Batugamping
Formasi Pamutuan di Lembar Pangandaran, yang
mengandung foraminifera jenis bentos dan
plangton, ganggan dan kepingan kerang.
Foraminifera plangtonnya menunjukan umur
Miosen Tengah (N12 - N13) dan lingkungannya
laut dangkal dan terbuka. Satuan in terdapat di
bagian selatan dan tenggara Lembar, membentuk
suatu morfologi karst. Tebal satuan berdasarkan
penampang geologi sekitar 500 m. Anggota
Batugamping menjemari dengan Anggota Tuf
Napalan Formasi Pamutuan dan menindih
Formasi Jampang secara selaras.
Program Studi Teknik Geologi, Fakultas Teknik – Universitas Pakuan 5
6. Formasi Bentang
Terdiri dari batupasir gampingan, batupasir
tufan, besisipan serpih dan mengandung lensa batugamping. Batugamping ini merupakan lensa pada batupasir gampingan, fosil foraminifera kecil yang terdapat dalam batupasir gampingan
yang menunjukan umur Miosen Akhir bagian
bawah (N17-N18), lingkungan pengendap annya neritik. Tebal satuan berdasarkan penampang geologi tidak lebih dari 800 m. Sebarannya terutama di bagian barat, tengah dan utara lembar peta.
7. Batuan Gunungapi Muda
Terdiri dari breksi gunungapi, lava dan tuf. Umur satuan batuan ini dikorelasikan dengan batuan yang sama di Lembar Tasikmalaya yaitu Plio-Plistosen. Sebarannya di bagian barat laut lembar peta.
8. Aluvium
Merupakan endapan sungai dan pantai
berupa lanau, pasir, kerikil dan kerakal.
Ketebalan satuan ini mulai dari satu sampai
beberapa meter. Sebarannya di beberapa tempat
tepi sungai besar dan pantai Cipatujah.
2.1.2. Stratigrafi Daerah Penelitian
Berdasarkan pengamatan, pengukuran serta ciri- ciri batuan yang tersingkap di lapangan,
maka satuan batuan di daerah penelitian dibedakan menjadi 4 (empat) satuan batuan, dimulai dari yang tua ke muda yaitu:
1. Satuan Batuan Tufa dan Lava
2. Satuan Batuan Batugamping Pasiran
3. Satuan Batuan Batupasir, Batugamping
dan Tufa.
4. Satuan Endapan Aluvial Sungai
Gambar 2.3. Peta Geologi Daerah Penelitian Tabel
Tabel 2. Kolom Stratigrafi Daerah Penelitian
Umur Zonasi J.A.
Postuna Litologi Satuan Batuan
Lingkungan
Pengendapan Zaman Kala
Ku
art
er Holosen Satuan Endapan Aluvial
Satuan Batuan Batupasir,
Batugamping dan Tufa
Satuan Batuan
Batugamping pasiran
Satuan Batuan Tufa dan
Lava
Darat
Laut Dangkal
Laut Dangkal
Darat
Plistosen N23 N22
T
e
r
s
i
e
r
Pliosen
N21
N20
N19
N18
M
i
o
s
e
n
Ak
hir
N17
N16
N15
Te
ng
ah
N14
N13
N12
N11
N10
N9
Aw
al
N8
N7
N6
N5
N4
1. Satuan Batuan Tufa dan Lava
Penamaan satuan ini di dasarkan atas ciri fisik
litologi yang dijumpai di lapangan berupa
singkapan batuan tufa sebagai penyusun utama dan
singkapan lava.
Satuan batuan ini tersebar dibagian Timur
Laut daerah penelitian. Menempati 16% dari luas
daerah penelitian dan pada peta diberi warna coklat
muda. Tersingkap di sepanjang sungai Ci
Leuwilieur, Ci Nunjang dan Desa Setiawaras.
Kedudukan satuan batuan ini tidak begitu jelas
namun ditafsirkan sama dengan batuan diatasnya
yang lebih muda dengan arah umum jurus N300E-
N350E dengan kemiringan 150-170. Ketebalan
satuan ini diukur dari rekonstruksi penampang
geologi adalah 1150 m.
Tufa umumnya tidak berlapis berwarna kuning
berukuran debu halus-sedang, bentuk buitr
membundar, sementasi silika. Secara mikroskopis
batuan tufa memperlihatkan warna abu-abu saat
sejajar nikol dan berwarna abu-abu kehitaman saat
silang nikol, memiliki ukuran butir 0,25-1,1mm,
bentuk butirnya menyudut tanggung, kemas
terbuka, massa dasar gelas, dengan mineral utama
orthoklas dan kuarsa, matriks berupa litik. Terdiri
dari Litik ±10%, Mineral lempung ±5%,
Orthoklas ±5%, Mineral Opak ±5%, Kuarsa ±5%,
dan masa dasar Gelas ±70%. Berdasarkan hasil
analisa sayatan tipis batuan yang diambil pada
lokasi pengamatan BA-81, diperoleh nama Tuf
Gelas (Pettijohn, 1975).
Lava berwarna abu-abu kehitaman, derajat
kristalisasi hypokristalin, besar butir afanitik,
bentuk kristal subhedral-anhedral, equigranular
dengan komposisi mineral terdiri dari: plagioklas,
hornblende, opak, gelas. Secara mikroskopis
sayatan tipis lava memperlihatkan warna trasparan
Program Studi Teknik Geologi, Fakultas Teknik – Universitas Pakuan 6
saat sejajar nikol dan abu-abu saat silang nikol,
derajat kristalisasi hypokristalin, ukuran butir
afanitik, bentuk butir subhedral - euhedral, kemas
inequigranular, tekstur umum porfiritik,
komposisi mineral plagioklas, orthoklas, opak,
gelas, hornblende, masa dasar kristal. Sayatan ini
disusun oleh Orthoklas ±5%, Plagioklas
±65%, Mineral opak ±15%, Gelas ±10%,
Hornblend
±5%. Nama batuan: Andesite (William, 1952).
Umur satuan batuan ini ditentukan berdasarkan posisi stratigrafi dan kesebandingan
litostratigrafi dengan peneliti terdahulu. Berdasarkan posisi stratigrafinya, satuan batuan tufa dan lava tertindih secara tidak selaras
dibawah satuan batuan batugamping pasiran yang
berumur N9 -N13 yang menjadikan satuan batuan tufa dan lava ini berumur lebih tua dari N9-N13. Berdasarkan keseban-dingan litostratigrafi, satuan batuan tufa dan lava memiliki kesamaan dengan ciri litologi dengan Formasi Jampang yang menurut Supriatna, dkk (1992) berumur
Miosen Awal.
Berdasarkan posisi stratigrafi dan kesebandingan
litostratigrafi dengan peneliti terdahulu maka
dapat disimpulkan bahwa umur satuan batuan
tufa dan lava adalah Miosen Awal.
Lingkungan pengendapan satuan batuan
tufa dan lava ditentukan berdasarkan pada ciri
fisik litologinya. Kenampakan ciri fisik litologi
satuan batuan ini terdiri dari tufa dan lava,
dimana batuan-batuan tersebut berasal dari batuan
piroklastik produk aktivitas gunungapi,
sedangkan lava yang dijumpai memper- lihatkan
struktur sheeting joint dan tidak dijumpai lava
yang berstruktur bantal. Maka dapat disimpulkan
bahwa satuan batuan tufa dan lava ini hasil
produk gunungapi yang terbentuk di darat dengan
demikian dapat ditafsirkan bahwa satuan batuan
ini di endapkan di lingkungan darat.
Kedudukan stratigrafi satuan batuan tufa dan
lava dengan satuan batuan di bawahnya tidak
diketahui karena satuan batuan ini adalah satuan
batuan yg tertua di daerah penelitian. Sedangkan
kedudukan stratigrafi satuan ini dengan satuan
diatasnya yaitu satuan batuan batugamping
pasiran adalah tidak selaras karena kedudukan
stratigrafi yang berbeda.
Satuan batuan tufa dan lava yang tersingkap
di daerah penelitian dapat disebandingkan dengan
Formasi Jampang (Supriatna, S., dkk.,1992) hal
ini didasarkan pada ciri litologinya yang sama
dengan ciri litologi Formasi Jampang.
2. Satuan Batuan Batugamping Pasiran
Penamaan satuan ini didasarkan atas ciri fisik
litologi yang dijumpai di sepanjang lintasan
pemetaan berupa batugamping pasiran.
Satuan batuan ini berada dibagian baratlaut daerah
penelitian dan menempati sekitar 13% dari luas
daerah penelitian dan pada peta geologi diberi warna
biru. Satuan batuan ini tersingkap di sepanjang
sungai Ci- Beber dan Ci Sodong serta di sekitar Desa
Bojongasih. Kedudukan satuan batuan ini tidak
begitu jelas namun ditafsirkan sama dengan batuan
diatasnya yang lebih muda dengan arah umum jurus
N300E-N350E dengan kemiringan 150-200. Ketebalan
satuan ini diukur dari rekonstruksi penampang
geologi adalah 650 m.
Batugamping umumnya tersingkap di tepi jalan dan
di sungai dalam kondisi yang lapuk - segar, masif
dengan warna kuning, ukuran butir halus. Konstituen
utama foraminifera, komposisi mineral karbonat.
Secara mikroskopis sayatan tipis batuan
memperlihatkan warna putih kecoklakan saat sejajar
nikol dan abu-abu saat silang nikol, konstituen utama
kerangka ukuran butir 0,0825-1,1mm, secara umum
hubungan butirnya mengambang, bentuk butir
menyudut tanggung, pemilahan buruk, porositas
interpartikel. Komposisi terdiri dari Fossil ± 70%,
Kuarsa ±5%, dan mikrit sebagai masa dasar ±25%.
Nama batuan: Packstone (Dunham, 1962).
Umur satuan batuan ini ditentukan berdasarkan
persebaran fosil foraminifera planktonik yang
terkan- dung dalam conto batuan yang diambil pada
lokasi BA- 54 berupa kumpulan fosil-fosil: Orbulina
universa (D’ORBIGNY), Globorotalia mayeri
(CUSHMAN & ELLISOR), dan Orbulina bilobata
(D’ORBIGNY) yang menunjukan umur kisaran N9 -
N13 atau Miosen Tengah. Sedangkan lingkungan
pengendapan satuan batuan ini ditentukan
berdasarkan kumpulan fosil foraminifera
bentoniknya yang terdiri dari Elphidium sp,
Cassidulina sp, Nonionella sp, yang menunjukan
lingkungan kedalaman 20-100 meter dibawah
permukaan laut atau pada zona neritik tengah.
Hubungan stratigrafi satuan batuan batugamping
pasiran dengan satuan batuan diatasnya yaitu satuan
batuan batupasir, batugamping dan tufa adalah tidak
selaras karena kedudukan batuannya tidak sama.
Satuan batuan batugamping pasiran yang
tersingkap di daerah penelitian dapat disebandingkan
dengan Formasi Kalipucang (Supriatna, S., dkk.,
1992) dikarenakan memiliki ciri litologi yang sama
yaitu berupa batugamping foraminifera dan
batugamping pasiran.
Program Studi Teknik Geologi, Fakultas Teknik – Universitas Pakuan 7
3. Satuan Batuan Batupasir, Batugamping, dan
Tufa
Penamaan satuan ini di dasarkan atas ciri fisik
litologi yang dijumpai di lapangan berupa
singkapan- singkapan batuan batupasir,
batugamping dan tufa.
Satuan batuan ini tersebar dibagian tengah lembar
peta menempati sekitar 70% dari luas daerah
penelitian dan pada peta geologi diberi warna
kuning. Satuan batuan ini tersingkap di sepanjang
sungai Ci Kalapa, Ci Palahlar, Ci Harus, Ci
Leuwilieur, Ci Sodong, disekitar Desa Sarimanggu
dan Desa Maruyung. Kedudukan jurus batuan
berkisar N300E-N600E dengan kemiringan batuan
berkisar antara 15º-25º. Ketebalan satuan batuan ini
diukur dari penampang geologi dan diperoleh
ketebalan sekitar 1250 m.
Secara megaskopis batupasir, berwarna kuning
hingga keabuan, ukuran butir pasir halus - sedang
(1/8 - 1/2 mm), bentuk butir membulat tanggung,
kemas tertutup, pemilahan buruk, sementasi
karbonat, kom- posisi mineral yang terlihat yaitu
kuarsa dan fosil. Secara mikroskopis sayatan tipis
batuan batupasir memperlihatkan warna putih
kecoklakan saat sejajar nikol dan abu-abu saat silang
nikol, ukuran butir 0,1- 0,825 mm, bentuk butirnya
menyudut tanggung - membundar, pemilahan buruk,
kemas bersentuhan. Komposisi mineral Karbonat
& Fosil ± 30%, Kuarsa ±15%, Plagioklas ±15%,
Litik ±20%, Opak ±15%, dan Mineral lempung
sebagai masa dasar ±5%. Nama batuan: Calcareous
Lithic Arenite (Gilbert, 1954).
Secara megaskopis batugamping berwarna putih
hingga kuning, ukuran butir halus. Konstituen
utama kerangka, komposisi mineral karbonat.
Secara mikroskopis sayatan tipis batugamping
memperlihatkan warna putih putih keabu-abuan
saat sejajar dan silang nikol, konstituen utama
kerangka, jenis butir kerangka terumbu, ukuran
butir 0,0825-1,1 mm, secara umum hubungan
butirnya mengambang, bentuk butir menyudut
tanggung, pemilahan buruk, keadaan fosil utuh
hingga pecah-pecah, porositas interpartikel.
Komposisi terdiri dari Cangkang fossil ±75%,
Kuarsa ±15%, dan Mikrit ±10%. Nama batuan:
Boundstone (Dunham, 1962).
Tufa secara megaskopis berwarna putih
berukuran debu halus-sedang, bentuk butir
membundar, pemilahan baik, sementasi silika.
Secara mikroskopis sayatan batuan tufa
memperlihatkan warna abu-abu saat sejajar nikol
dan berwarna abu-abu kehitaman saat silang nikol,
memiliki ukuran butir 0,25-1,1mm, bentuk
butirnya menyudut tanggung, kemas terbuka,
massa dasar gelas, dengan mineral utama orthoklas,
kuarsa dan plagioklas, matriks litik. Terdiri dari
Litik ±20%, Orthoklas ±20%, Opak ±5%, Kuarsa
±20%, Plagioklas 10%, dan gelas sebagai masa
dasar ±5%. Nama batuan : Tuff Crystall (Pettijohn,
1975).
Umur satuan batuan ini ditentukan berdasarkan
kumpulan fosil foraminifera planktonik yang
terkan- dung dalam conto batuan yang diambil pada
lokasi BA- 9 dan BA-66 berupa: Orbulina universa
(D’ORBIGNY), Globigerinoides extremus (BOLLI
& BERMUDEZ), Globorotalia menardii (BOLLI),
Orbulina bilobata (D’ORBIGNY) yang menunjukan
umur kisaran N16-N19 atau Miosen Akhir - Awal
Pliosen.
Lingkungan pengendapan satuan batuan ini
ditentukan berdasarkan sebaran fosil foraminifera
bentonik yang mewakili satuan batuan ini dijumpai
kumpulan dari fosil-fosil Nodosaria sp, Robulus sp,
Elphidium sp, Nodosarella sp, yang menunjukan
kedalaman sekitar 30 - 91 meter dibawah
permukaan laut atau pada zona neritik tengah.
Hubungan stratigrafi satuan batuan batupasir,
batugamping dan tufa dengan satuan batuan
diatasnya yaitu satuan endapan aluvial adalah tidak
selaras yang dibatasi oleh bidang erosi.
Satuan batuan batupasir, batugamping dan tufa
yang tersingkap di daerah penelitian dapat diseban
dingkan dengan Formasi Bentang (Supriatna, 1992)
dikarenakan memiliki ciri litologi yang sama yaitu
terdiri dari batupasir gampingan, batupasir tufan,
tufa, bersisipan serpih dan lensa-lensa batugamping.
4. Satuan Endapan Aluvial
Penamaan satuan ini didasarkan pada material
aluvial sungai yang berukuran lempung hingga
bongkah yang bersifat lepas sebagai penyusun satuan
ini. Satuan ini menempati 4% dari luas daeah
penelitian dan diberi warna abu-abu pada peta
geologi. Umumnya tersebar di sepanjang Sungai
Cikalapa.
Satuan endapan aluvial disusun oleh material
sungai berukuran lempung, pasir, kerikil, kerakal
sampai bongkah dengan bentuk menyudut tanggung
sampai membulat yang berasal dari hasil pelapukan
dan erosi satuan-satuan batuan yang lebih tua, yaitu
dari batuan Formasi Jampang, Formasi Kalipucang
dan Formasi Bentang.
2.3. Struktur Geologi
2.3.1. Struktur Geologi Regional
Struktur geologi regional yang terdapat di
Pulau Jawa merupakan manifestasi subduksi antara
Lempeng Samudra Indo-Astralia dan Lempeng
Program Studi Teknik Geologi, Fakultas Teknik – Universitas Pakuan 8
Eurasi. Hasil interaksi ini berupa jalur magmatik
yang membentang dari Pulau Sumatra ke arah
timur hinga Nusa Tenggara yang dikenal sebagai
Busur Sunda. Selain membentuk jalur magmatik,
interaksi lempeng-lempeng tersebut juga
menghasilkan pola-pola struktur.
Pulunggono dan Martodjojo (1994)
menyatakan bahwa terdapat tiga pola struktur
dominan yang berkembang di Pulau Jawa, yaitu:
1. Pola Meratus, berarah timurlaut-baratdaya
terbentuk pada 80-53 juta tahun yang lalu
(Kapur Akhir - Eosen).
2. Pola Sunda, berarah utara - selatan terbentuk
53-32 juta tahun yang lalu ( Eosen Awal -
Oligosen Awal)
3. Pola Jawa, berarah barat - timur terbentuk 32
juta tahun yang lalu - sekarang (Oligosen
Akhir – Holosen), merupakan pola struktur
yang paling muda, memotong dan merelokasi
pola struktur Meratus dan pola struktur Sunda.
Gambar 3.4. Pola Struktur Pulau Jawa
2.3.2. Struktur Geologi Daerah Penelitian
1. Struktur Kekar
Struktur kekar yang berkembang di daerah
penelitian adalah jenis kekar gerus (shear
fracture). Di daerah penelitian kekar gerus
dijumpai berarah N30o E dan N3400E dengan
kemiringan berkisar antara 700-900.
2. Struktur Lipatan
Berdasarkan hasil pengamatan unsur-unsur
struktur geologi di daerah penelitian, dapat
diketahui bahwa di daerah penelitian terdapat
lipatan yaitu Lipatan Homoklin. Adapun bukti-
bukti adanya struktur lipatan homoklin di daerah
penelitian di dasarkan atas data lapangan berupa
arah kedudukan batuan yang relatif sama berarah
baratdaya - timurlaut dengan kemiringan kearah
selatan berkisar antara 15o-25o.
3. Struktur Patahan
Berdasarkan hasil pengamatan unsur-unsur
struktur geologi di daerah penelitian, dapat
diketahui bahwa di daerah penelitian terdapat 2
(dua) sesar, yaitu: (a). Sesar Mendatar Cinunjang
dan (b). Sesar Mendatar Cikalapa. Penentuan sesar
di daerah penelitian didasarkan atas data lapangan
berupa indikasi sesar yang teramati, yaitu adanya
bidang sesar, kekar-kekar.
a). Sesar Mendatar Cinunjang
Penamaan sesar mendatar Cinunjang
berdasarkan bukti sesar yang dijumpai di Sungai
Cinunjang dengan arah timurlaut-baratdaya
dengan Panjang sesar ± 5.6 km.
Adapun indikasi atau struktur penyerta dari
sesar mendatar Cinunjang di lapangan berupa:
1. Kedudukan bidang sesar pada batuan tufa di
BA- 81 dengan arah N 25o E/60o, pitch 10o,
plunge 27o Trend N 80o E di Sungai
Cinunjang.
2. Kekar gerus pada batuan tufa di BA-86
dengan arah umum N 30oE. 3. Kelurusan Sungai Ci Leuwilieur.
Berdasarkan pergerakan relatifnya, maka
sesar mendatar Cinunjang adalah Sinistral Strike
Slip Fault.
b). Sesar Mendatar Cikalapa
Penamaan Sesar Mendatar Cikalapa
berdasarkan bukti sesar yang dijumpai di Sungai
Cikalapa dengan arah sesar baratlaut-tenggara dan
Panjang sesar sekitar 4.4km.
Adapun indikasi adanya sesar mendatar
Cikalapa di lapangan antara lain:
1. Kedudukan yang tidak teratur pada sugai Ci
Kalapa
2. Kedudukan bidang sesar pada batuan tufa di BA- 81 dengan arah N 145o E/56o, pitch 30o, plunge 20o trend N 300o E di Sungai
Cinunjang.
3. Kelurusan Sungai Cikalapa.
Berdasarkan pergerakan relatifnya, maka sesar
mendatar Cikalapa adalah jenis sesar mendatar
Dextral Strike Slip Fault.
2.3.3. Umur dan Mekanisme Pembentukan
Struktur Daerah Penelitian
Berdasarkan hasil pengukuran data
kedudukan batuan yang terdapat di daerah
penelitian diketahui bahwa jurus lapisan batuan
umumnya berkisar N30oE dan N60oE, sehingga
gaya yang berpengaruh yang terjadi di daerah
penelitian berkisar N 155oE atau berarah baratlaut-
tenggara. Adapun urutan pembentuk- an struktur
geologi di daerah penelitian di awali dengan
pembentukan lipatan homoklin yang berarah
baratdaya- timurlaut dan kemudian dilanjutkan
dengan pembentuk- an sesar mendatar Cinunjang
Program Studi Teknik Geologi, Fakultas Teknik – Universitas Pakuan 9
dan diakhiri oleh pemben- tukan sesar mendatar
Cikalapa. Keseluruhan struktur geologi yang
terdapat di daerah penelitian terjadi dalam 1
periode tektonik, yaitu kala Pliosen-Plistosen
dengan arah gaya N1550E atau baratlaut-tenggara.
Apabila dikaitkan dengan arah gaya Pulau
Jawa pada Oligosen Akhir - Plistosen yang
berarah utara- selatan, maka gaya yang bekerja di
daerah penelitian yaitu baratlaut-tenggara adalah
merupakan vektor gaya dari gaya resultan Pulau
Jawa yang berarah utara- selatan.
2.4. Sejarah Geologi
Sejarah geologi daerah penelitian dimulai
pada kala Oligosen Akhir yaitu dengan
terbentuknya busur gunungapi hasil tumbukan
lempeng India-Australia dengan lempeng Eurasia
pada kala Oligosen Akhir hingga Awal Miosen
yang kemudian materialnya diendapkan sebagai
Formasi Jampang berupa tuf dan lava.
Pada pertengahan Miosen Bawah bagian atas
daerah penelitian mulai terjadi fase tektonik aktif
(orogenesa) yang menyebabkan satuan batuan tuf
dan lava (Formasi Jampang) mengalami perlipatan
dan pengangkatan dan aktivitas tektonik ini
berakhir pada kala akhir Miosen Bawah.
Kemudian pada N9 atau awal Miosen Tengah mulai ada pengendapan kembali yaitu satuan batuan batugamping pasiran (Formasi Kalipucang) yang diendapkan di lingkungan laut dangkal.
Pengendapan satuan batuan Formasi Kalipucang
berakhir pada N13 atau Miosen Tengah bagian akhir.
Pada N14 daerah penelitian mengalami aktivitas tektonik (orogenesa) yang mengakibatkan batuan-
batuan dari Formasi Jampang dan Formasi
Kalipucang terlipat dan terangkat. Orogenesa ini
berhenti pada N15.
Pada N16 atau pertengahan Miosen Akhir di daerah penelitian mulai terjadi pengendapan satuan batuan batupasir, batu gamping, dan tufa (Formasi Bentang) pada lingkungan laut dangkal
dan pengendapan satuan batuan ini berakhir pada
N19.
Pada N20 atau awal kala Plistosen Tengah daerah penelitian mengalami orogenesa kembali yang menga- kibatkan batuan-batuan dari Formasi Jampang, Formasi Kalipucang dan Formasi Bentang mulai terlipat menghasilkan lipatan homoklin dan diperkirakan pada akhir Pliosen terjadi pensesaran berupa sesar mendatar Cinunjang dan sesar mendatar Cikalapa.
Pada kala Plistosen diperkirakan daerah
penelitian sudah menjadi daratan sehingga proses-
proses ekso- genik (pelapukan, erosi dan
sedimentasi) mulai bekerja terhadap batuan-batuan
dari Formasi Jampang, Formasi Kalipucang dan
Formasi Beser yang hasilnya sebagian diendapkan
sebagai endapan permukaan dan sebagian masuk
kedalam sungai-sungai yang ada di daerah
penelitian dan diendapkan sebagai endapan
alluvial sungai dan proses proses eksogenik ini
terus berlangsung hingga saat ini.
2.5. Potensi Sumberdaya Tufa
Berdasarkan hasil pemetaan geologi di daerah
Karangmekar dan sekitarnya, Kecamatan Karang
nunggal, Kabupaten Tasikmalaya, Propinsi Jawa
Barat maka aspek sumberdaya bahan galian yang
ekonomis yang terdapat di daerah penelitian
adalah batuan tufa dimana penyebaran dan
pelamparannya cukup luas sehingga dapat
dimanfaatkan sebagai bahan baku industri.
Tufa Merupakan bahan galian yang cukup
banyak mengandung silika amorf yang dapat larut
di air atau dalam larutan asam. Tufa pada
umumnya terbentuk dari batuan vulkanik yang
mengandung feldspar dan silika. Sebagai bahan
bangunan, tufa mempunyai sifat-sifat khas, sifat
tufa yang terpenting yaitu apabila dicampur
dengan kapur padam (kapur tohor) dan air akan
mempunyai sifat seperti semen, yaitu mengikat.
2.5.1. Perhitungan Sumberdaya Tufa
Dalam perhitungan sumber daya bahan
galian di daerah penelitian dibagi menjadi dua
tahapan, yaitu:
1. Tahapan perhitungan luas. Dalam perhitungan
luas digunakan metode gridding, yaitu
perhitungan luas yang membagi area pada peta
yang berbentuk bujur sangkar.
2. Tahapan perhitungan volume. Dalam
perhitungan volume digunakan metode kontur menurut B.C.Craft and M.F.Hawkins (1959).
Gambar 5, Model perhitungan volume
Sumber : Applied Petroleum Reservoir Engineering
Program Studi Teknik Geologi, Fakultas Teknik – Universitas Pakuan 10
Tabel 3. Perhitungan Metoda Kontur (Craft,B.C.
Craft dan Hawkin, H.F., 1959)
Sumber : Applied Petroleum Reservoir Engineering
Keterangan:
* : Banyaknya kontur tergantung dari data
kontur di peta antara kontur batas
perhitungan dengan titik puncak.
** : Jika A1/A0 > 0.5, maka rumus yang digunakan adalah
V1 = "#
(A0 + A1 + √A0. 𝐴1)
*** : Jika A1/A0 < 0.5, maka rumus yang digunakan adalah
V1 = "#
(A0 + A1)
Analisa kimiawi dilakukan untuk mengetahui
kandungan senyawa apa saja yang terdapat pada
batu tufa yang ada di daerah penelitian. Hasil dari
analisa kimiawi batuan tufa ini kemudian di plot
kedalam kurva Avgustinik untuk mengetahui jenis
peruntukannya.
Dalam melakukan analisis kimiawi untuk
studi khusus ini dapat dilakukan dengan menggunakan analisis ICP (Inductivetively Coupled Plasma) adapun hasilnya akan membantuk dalam menentukan kandungan senyawa oksida yang terdapat dalam batuan tufa tersebut. Sampel yang diambil dianalisa
kandungan senyawa oksidanya seperti kandungan
SiO2, TiO2, MgO, Na2O3, CaO, Fe2O3, Al2O3, Na2O, K2O.
Metoda Avgustinik digunakan untuk
mengetahui jenis peruntukan dari tufa yang
terdapat di daerah penelitian dari sampel batuan
yang dianalisa kadar atau unsur kimiawinya.
Gambar 6. Grafik dari Metoda Avgustinik
Keterangan Grafik:
1. Untuk bahan tahan api jenis “Shamot”.
2. Untuk keramik, gerabah halus padat dan
tahan asam.
3. Untuk gerabah halus lunak dan terrakota.
4. Untuk pembuatan genteng.
5. Untuk Bata Klinker.
6. Untuk Bata Biasa.
Cara perhitungan untuk di plot ke dalam diagram
avgustinik dilakukan dengan langkah-langkah
sebagai berikut:
1) Hitung persen kumulatif dari setiap kadar
senyawa oksida daric onto batuan yang
dianalisa.
2) Rubahlah persen kumulatif yang didapat
kedalam satuan grol dengan cara membagi
persen kumulatif senyawa oksida dengan berat
molekulnya.
3) Sebandingkan kadar Al2O3 (sebagai nilai Z)
dengan SiO2 (sebagai nilai X) sehingga
rumusnya menjadi Z/X adalah sebagai
Ordinat.
4) Nilai Absis dihasilkan dari persamaan sebagai
berikut:
∑ R 2O + RO + Fe2O3 = d + e + b + c + a …….
(nilai absis)
dimana R2O adalah :
kadar grol Na2O (d)
kadar grol K2O (e)
RO adalah : kadar Fe2O3 (a)
kadar MgO (b)
kadar CaO (c)
Program Studi Teknik Geologi, Fakultas Teknik – Universitas Pakuan 11
SiO2 63.01863019 60.08 1.0489 0.0349 0.0846
Na2O 1.20601206 61.98 0.0194
K2O 1.45801458 94.2 0.0155
Fe2O3 1.40401404 159.69 0.0088
CaO 2.02502025 56.08 0.0361
MgO 1.60201602 40.3 0.0397
Al203 10.24210242 101.96 0.1004
TiO2 0.14400144 79.87 0.0018
LOl 8.532085321
H2O-
10.36810368 18.02 0.5753
Unsur
Kimia Persen Kumulatif
Berat
Molekulgrol R₂O RO
Selanjutnya masukan (plot) kedalam diagram
avgustinik, sehingga dari masing-masing sampel
batuan yang dianalisa dapat diketahui jenis
peruntukannya.
2.5.2. Perhitungan Sumber Daya Tufa
Daerah Penelitian
Perhitungan sumber daya tufa menggunakan metode perhitungan berdasarkan B.C Craft dan M.F. Hawkins (1959), dan hasil perhitungan luas dan volume kotor tufa di daerah penelitian disajikan dalam Tabel 4, dan perhitungan untuk volume tanah penutup di daerah penelitian di sajikan dalam Tabel 5.
Tabel 4. Perhitungan Volume Kotor
Tufa
Kontur Luas (m²) Interval
Kontur
Perbandingan Luas
Area (ratio)
Tipe
Geometri Volume Kotor (m³)
287,5 94,801.97 - - - -
275 583,483.02 12,5 0.162475969 Piramida 4,239,281.18
262,2 561,685.28 12,5 1.038807753 Trapesium 7,156,869.61
250 7,969,273.93 25 0.070481361 Piramida 106,636,990.10
225 273,857.41 25 29.10008527 Trapesium 81,003,677.45
200 141,010.21 25 1.942110422 Trapesium 5,094,824.38
175 277,372.58 25 0.508378347 Trapesium 5,134,593.89
125 60,171.26 50 4.609718987 Trapesium 7,778,884.46
100 34,886.19 25 1.724787209 Trapesium 1,173,949.04
Total Volume Kotor 218,219,070.11
Tabel 5. Perhitungan Tanah Penutup
Ketebalan (m) Luas (m²) Volume (m³)
0,5 24,537.82 12,268.91
1 7,560,663.02 7,560,663.02
1,5 1,234,322.96 1,851,484.45
Jumlah 9,424,416.37
Volume Bersih = Volume Kotor - Tanah
Penutup
= 218,219,070.11 - 9,424,416.37
= 208,794,653.74 m³
Tonase = Volume Bersih x Berat
Jenis
Berat Jenis Tuf = 2500 kg/m3
= 208,794,653.74 x 2500
= 52.198.632.500 Kg
= 52.198.632,5 Tonase
Setelah menghitung luasan dan volume, maka
selanjutnya adalah menganalisa kimia batuan tufa
di daerah penelitian guna mengetahui
peruntukannya dengan metoda avgustinik. Dari 3
sampel yang diuji diperoleh hasil sebagai berikut
Tabel 6. Hasil pehitungan dengan
metoda avgustinik di sampel BA-11
R2O = grol Na2O + grol K2O = 0.0451
RO = grol Fe2O3 + grol MgO + grol CaO
= 0.06908
Nilai ordinat = grol Al2O3 / grol SiO2
= 0.0966502 = 0.1
Nilai absis = R2O + RO + Fe2O3 = 0.11418 = 0.1
Tabel 7. Hasil pehitungan dengan metoda avgustinik di
sampel BA-18
R2O = grol Na2O + grol K2O
= 0.0349
RO. = grol Fe2O3 + grol MgO + grol CaO
= 0.0846
Nilai ordinat = grol Al2O3 / grol SiO2
= 0.0957193 = 0.1
Nilai absis = R2O + RO + Fe2O3 = 0.1195 = 0.1
SiO2 60.982191 60.08 1.015 0.0451 0.06908
Na2O 1.502069 61.98 0.0242
K2O 1.969779 94.2 0.0209
Fe2O3 1.690952 159.69 0.01058
CaO 2.64436 56.08 0.0471
MgO 0.4587156 40.3 0.0114
Al203 10.001799 101.96 0.0981
TiO2 0.1529052 79.87 0.0019
LOl 10.343587
H2O-
10.253643 18.02 0.569
ROUnsur
Kimia Persen Kumulatif
Berat
Molekulgrol R₂O
Program Studi Teknik Geologi, Fakultas Teknik – Universitas Pakuan 12
Tabel 8. Hasil pehitungan dengan metoda
avgustinik di sampel BA-24
R2O = grol Na2O + grol K2O
= 0.0272
RO = grol Fe2O3 + grol MgO + grol CaO
= 0.0875
Nilai ordinat = grol Al2O3 / grol SiO2
= 0.0956841 = 0.1
Nilai absis = R2O + RO + Fe2O3
= 0.1214 = 0.1
Setelah itu di ploting ke dalam diagram
avgustinik untuk mengetahui peruntukan batuan
tufa di daerah penelitian cocoknya digunakan
sebagai bahan baku industri, berikut hasil ploting
pada diagram avgustinik:
Gambar 7. Grafik hasil perhitungan analisa
kimia di BA-11, BA-18 dan BA-24.
Maka dari hasil ploting menggunakan
diagram avgustinik di dapatkan hasil 5 dan 6.
Menjadikan batuan tufa di daerah penelitian
cocok digunakan untuk pembuatan bata klinker
dan bata biasa.
III. KESIMPULAN DAN SARAN
3.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah
dilakukan berupa pemetaan geologi permukaan si
daerah Karangmekar dan Sekitarnya, Kecamatan
Karang- nunggal, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa
Barat yang berkaitan dengan geomorfologi,
stratigrafi, struktur geologi dan potensi
sumberdaya batuan fufa, maka dapat disimpulkan
sebagai berikut:
1. Geomorfologi daerah penelitian secara
morfo- genesa dapat dibagi menjadi 2
satuan, yaitu; (a). Satuan geomorfologi
perbukitan lipatan, sub- satuan pebukitan
homoklin berstadia dewasa dan (b). Satuan
geomorfologi dataran aluvial berstadia
muda. Pola aliran sungai yang terdapat di
daerah penelitian berpola rektangular dan
stadia erosi sungai muda dan dewasa.
2. Tatanan batuan yang terdapat di daerah penelitian dari yang tertua hingga termuda adalah: (1). Satuan batuan tufa dan lava (Formasi Jampang) berumur Miosen Awal
yang diendapkan di lingkungan darat; (2). Satuan batuan batugamping pasiran
(Formasi Kalipucang) berumur N9 -N13 atau Miosen Tengah yang diendapkan pada ke dalaman 20-100m atau neritik tengah; (3). Satuan batuan batupasir, batugamping dan
tufa (Formasi Bentang) berumur N16 - N19
atau Miosen Akhir - Pliosen yang diendapkan pada kedalaman 38-91m atau neritik tengah; (4). Satuan endapan aluvial sungai.
3. Struktur geologi yang dijumpai di daerah
penelitian berupa struktur kekar, lipatan dan
patahan. Struktur kekar yang dijumpai
adalah kekar gerus. Struktur lipatan berupa
lipatan homoklin yang berarah baratdaya-
timurlaut dan struktur patahan berupa sesar
mendatar Cinunjang dan sesar mendatar
Cikalapa. Keseluruhan struktur geologi
terjadi pada kala Pliosen-Plistosen dengan
arah gaya utama N1550E atau berarah
baratlaut- tenggara.
4. Cadangan sumberdaya bahan galian tufa
yang terdapat di daerah penelitian
berdasarkan perhitungan dengan metode
konturing diperoleh cadangan sebesar
52.198.632,5 Tonase sedangkan
berdasarkan analisa kimiawi batuan tufa
dengan metoda avgustinik, diketahui bahwa
sumberdaya batuan tufa yang terdapat di
daerah penelitian dapat dimanfaatkan
sebagai bahan baku indsutri yaitu untuk
SiO2 65.43154495 60.08 1.089 0.0272 0.0875
Na2O 0.933070159 61.98 0.015
K2O 1.157365871 94.2 0.0122
Fe2O3 1.085591244 159.69 0.0067
CaO 1.650816436 56.08 0.0294
MgO 2.072492374 40.3 0.0514
Al203 10.6226449 101.96 0.1042
TiO2 0.161492913 79.87 0.002
LOl 6.335139063
H2O-
10.5598421 18.02 0.586
ROgrolUnsur
Kimia Persen Kumulatif Berat
MolekulR₂O
Program Studi Teknik Geologi, Fakultas Teknik – Universitas Pakuan 13
pembuatan bata klinker dan bata biasa.
3.2 Saran
Saran yag bisa penulis berikan adalah
perlunya kajian yang lebih dalam lagi untuk
memanfaatkan sumber daya tufa di daerah
penelitian agar dapat di kelola secara lebih
efektif dan efisien, sehingga dapat menjadi mata
pencaharian baru bagi warga disekitar daerah
penelitian.
DAFTAR PUSTAKA
Avgustinik. A.I, 1983 Ceramics, Spanish,
Reverte.
Bakosurtanal, 1999, Peta Rupabumi Digital
Indonesia Lembar Cibalong No.
1308-134, , skala 1:25.000, Badan
Koordinasi Survey dan Pemetaan
Nasional, Bogor.
Bandy, O.I., 1967, Foraminiferal Indices in
Paleontology, Texas W. H.
Freemanand Company.
Bemmelen, R.W., van, 1949, The Geology of
Indonesia, Vol. IA: General Geology
of Indonesia and Adjacent
Archipelagoes, Government Printing
Office, The Hague, p.732.
Blow, W. H. and Postuma J. A. 1969. Range Chart,
Late Miosen to Recent Planktonic
Foraminifera Biostratigraphy,
Proceeding of The First.
Boltovskoy, E., Wright., R., 1976, Recent
Foraminifera, Buenos Aires, Dr., W.
Junk, b.v Publisher, 515 p.
Craft, B. C. Hawkins, M. F. 1959, Applied
Petroleum Reservoir Engineering, A
Simon & Schuster Company
Englewood Cliffs, New Jersey
Dunham, R. J., 1962, Classification of carbonate
rocks according to depositional
texture. In : Classification of Carbonate
Rocks (Ed. W.E. Ham), Am. Assoc. Pet.
Geol. Mem., 1, 108- 121.
Irawan, P. Handiman, I. 2016, Analisa Geologi
Teknik Dalam Perencanaan Bendung
Daerah Irigasi Parigi Kabupaten
Pangandaran, Jurnal Siliwangi Vol.2.
Tasikmalaya.
Iqbal, P., dan Yanti, D. E. 2014, Karakteristik Fisik
dan Kimia Lempung Barat Dalam
Penggunaannya Sebagai Bahan Baku
Pembuatan Keramik, Bandung,
Publikasi Ilmiah Pendidikan dan
Pelatihan Geologi, Vol. 10 No. 1.
Katili, J.A., 1975, Volcanism and plate tectonics
in the Indonesian Island arcs, Tectonophysics, Volume 26, Pages 165-188.
Lobeck, A. K., 1939, Geomorphology: An
Introduction to the Study of
Landscapes, Mc.Graw-Hill Book
Company, New York.
Martodjojo, S., 1984. Evolusi Cekungan Bogor,
Desertasi Doktor ITB, Program Pasca
Sarjana, Institut Teknologi Bandung,
Bandung, Tidak Diterbitkan.
Moody, J.D. and Hill, M.J., 1956, Wrench Fault
Tectonics, Bulletin of geology, Volume 67.
Noor, Djauhari, 2014, Geomorfologi, Penerbit Deepublish (CV Budi Utama), Jalan Kaliurang KM 9,3 - Yogyakarta 55581, hal. 326, ISBN 602280242-6.
Sudrajat, Adjat, Syafri, Ildrem, dkk, 2009,
Laporan Akhir Penelitian Hibah
Penelitian Strategis Nasional -
Karakteristik Sumber daya Geologi di
Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan
Sebagai Referensi Pengem bangan
Sumber Daya Alternatif, Bandung,
Departemen Pendidikan Nasional
Universitas Padjadjaran.
Supriatna, dkk., 1992, Peta Geologi Lembar
Karangnunggal, skala 1:100.000. Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi (P3G), Bandung.
Thornbury, William D., 1969, Principles of
Geomorphology, Second Edition, John
Willey and Sons Inc., New York,
London, Sydney, Toronto, 594p.
Williams, H., Turner, F.J., Gilbert, C.M., 1954,
Petrograpy, An Introduction to
TheStudy of Rock in Thin Sections,
W.H Freeman and Company, New
York.
Penulis :
1. Bei Hasbiana Azizah, ST. Alumni (2020)
Program Studi Teknik Geologi, Fakultas
Teknik – Universitas Pakuan, (E-mail :