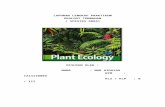Bufo melanostictus SEBAGAI SPESIES INDIKATOR TERHADAP KUALITAS LINGKUNGAN HUTAN PENDIDIKAN WANAGAMA
Transcript of Bufo melanostictus SEBAGAI SPESIES INDIKATOR TERHADAP KUALITAS LINGKUNGAN HUTAN PENDIDIKAN WANAGAMA
9
Bufo melanostictus SEBAGAI SPESIES INDIKATOR TERHADAP KUALITAS LINGKUNGAN HUTAN PENDIDIKAN WANAGAMA
Fikri Al-Mubarok
Abstrak
Amfibi merupakan kelas hewan yang sering digunakan sebagai indikator suatu lingkungan. Jika keanekaragaman jenis amfibi tinggi dan terdapat jenis-jenis tertentu yang jarang ditemukan maka suatu lingkungan dapat dikatakan masih dalam kondisi baik, sebaliknya jika terdapat jenis-jenis yang sering ditemukan maka suatu lingkungan dapat dikatakan memiliki kondisi yang buruk. Salah satu jenis amfibi yang hanya hidup pada lingkungan yang buruk yaitu jenis kodok buduk (Bufo melanostictus). Penelitian ini yaitu untuk membuktikan bahwa kodok buduk dapat digunakan sebagai bio-indikator di Hutan Pendidikan Wanagama. Untuk membuktikannya yaitu dengan mengetahui adanya pengaruh karakteristik lingkungan yang baik terhadap frekuensi kehadiran kodok buduk di Hutan Wanagama. Karakteristik lingkungan hutan diwakili oleh penutupan tajuk, penutupan tumbuhan bawah, jarak dari sumber air, jarak dari pemukiman, suhu dan kelembaban. Pengambilan data dilakukan dengan metode line transect dengan jumlah 3 garis yang diletakkan di dekat sumber air. Untuk mengetahui pengaruh karakteristik lingkungan hutan yang baik terhadap frekuensi kehadiran kodok buduk yaitu dengan menggunakan uji regresi. Hasil menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan dari karakeristik lingkungan hutan yang baik terhadap frekuensi kehadiran kodok buduk.
Kata kunci: Bufo melanostictus, bio-indikator, kondisi lingkungan hutan, Wanagama.
1. Pendahuluan
Hutan Pendidikan Wanagama I awalnya merupakan lahan kritis berupa kumpulan batu bertanah, mulai dibangun sejak tahun 1966 hingga akhirnya terbentuk hutan yang kompleks. Dalam pembangunan hutan Wanagama I oleh Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada termasuk cepat, karena suksesi yang terjadi di kawasan tersebut dipengaruhi oleh manusia. Namun, dalam kurun waktu 47 tahun Wanagama I masih dalam tahap berkembang ekosistemnya. Petak-petak di Wanagama I memiliki perbedaan dalam hal kondisi
lingkungannya termasuk kondisi vegetasi penyusunnya. Lokasi-lokasi Wanagama I tidak seluruhnya merupakan lahan yang tertutup hutan dan yang tertutup oleh hutan pun belum tentu memiliki lingkungan yang baik dan sesuai bagi kehidupan satwa liar.
Amfibi dapat berfungsi sebagai bio-indikator bagi kondisi lingkungan karena amfibi memiliki respon terhadap perubahan lingkungan (Stebbins & Cohen, 1997). Kodok Buduk (Bufo melanostictus) (Schneider, 1799) merupakan amfibi dari ordo anura (kodok dan katak). Amfibi merupakan anggota dari herpetofauna. Menurut Fitri (2002),
10
herpetofauna sangat menyukai tempat-tempat yang kondisi kelembabannya relatif tinggi dan dekat dengan badan air. Begitupun menurut Mistar (2008), amfibi dan reptil hidup di air dan darat, namun demikian kita harus memilih tempat-tempat yang diduga sebagai habitatnya. Antara lain, sungai-sungai besar maupun kecil, kolam-kolam kecil, kubangan hewan, kayu lapuk, dan akar banir yang terakumulasi dengan serasah daun.
Namun, lain halnya dengan spesies Bufo melanostictus, kodok jenis ini merupakan spesies yang paling tahan dengan kondisi habitat yang terganggu, spesies ini dapat digambarkan sebagai "generalis habitat" (Csurhes, 2010). B. melanostictus adalah salah satu jenis amfibi yang lebih menyukai habitat terbuka dan sering terjadi kepadatannya lebih tinggi di habitat terganggu sekitar pemukiman manusia daripada di hutan yang tidak terganggu, jenis ini sering ditemukan di kolam dan peternakan (Maskey dkk, 2002 dan Kentwood, 2007). Kusrini dan Remetwa (2007), menambahkan bahwa kodok jenis ini memiliki asosisasi yang kuat dengan tipe habitat yang terganggu. Bahkan Iskandar (1998) sendiri mengatakan bahwa habitat jenis ini selalu berada di dekat hunian manusia atau wilayah yang terganggu. Jenis ini tidak pernah terdapat di hutan hujan tropis.
Dari setiap kondisi petak di Wanagama I memiliki kondisi lingkungan yang berbeda dengan laju perkembangan hutan yang berbeda pula. Kawasan Wanagama I dilalui Sungai Oyo sebagai sumber air bagi satwa di dalamnya, namun belum tentu kualitas air dan kealamian Hutan Wanagama memiliki lingkungan yang baik. Kondisi suatu
lingkungan dapat dinilai dari parameter biotik dan abiotik. Secara praktis yaitu dapat mengunakan spesies indikator. Dalam penggunaan spesies indikator perlu sangat hati-hati, spesies indikator yang digunakan yaitu dari kelas amfibi dengan jenis B. melanostictus. Dengan melimpahnya jumlah individu jenis tersebut dapat mengindikasikan bahwa lingkungan Wanagama belum cukup dikatakan baik.
Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan Hutan Pendidikan Wanagama I dalam mengembangkan ekosistemnya, maka dilakukanlah penelitian ini. Dalam pelaksanaannya, deskripsi tentang kualitas lingkungan di Wanagama direpresentasikan oleh tiap-tiap petak. Untuk mengetahui petak-petak di Wanagama yang memiliki lingkungan hutan yang baik dan yang buruk, dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan menggunakan spesies indikator sebagai parameter dalam mengukur kualitas lingkungan hutan di Wanagama. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi karakteristik lingkungan hutan ditemukannya Bufo melanostictus di Wanagama, mengetahui frekuensi kehadiran Bufo melanostictus pada petak-petak di Hutan Pendidikan Wanagama, lalu mengetahui apakah Bufo melanostictus dapat dijadikan sebagai indikator lingkungan hutan pada petak-petak di Hutan Pendidikan Wanagama. Maka hipotesisnya adalah Bufo melanostictus dapat dijadikan indikator lingkungan Hutan Wanagama.
Untuk menilai baik buruknya suatu karakteristik lingkungan hutan yaitu melalui;
persen penutupan tajuk,
11
persen penutupan tumbuhan bawah,
jarak terhadap sumber air, jarak terhadap pemukiman
manusia, temperatur, dan kelembaban.
Karakteristik lingkungan hutan yang baik ditunjukkan oleh tingginya persentase penutupan tajuk, rendahnya persentase penutupan tumbuhan bawah, dekatnya jarak terhadap sumber air, jauhnya jarak dari pemukiman manusia, dan tingginya kelembaban udara. Sedangkan data temperatur sebagai data nominal yang akan membantu mendapatkan gambaran tambahan karakteristik lingkungan hutan ditemukannya B. melanostictus.
Manfaat dari penelitian ini yaitu diharapkan mampu memberi informasi mengenai petak-petak mana saja di Wanagama yang lingkungan hutannya baik dan buruk melalui frekuensi kehadiran Bufo melanostictus sebagai spesies indikator Implikasi dari penelitian ini yaitu dapat membantu dalam pengelolaan kawasan Wanagama dengan memudahkan dalam memprioritaskan
tujuan pengelolaan pada setiap petak-petaknya, serta dapat memberikan informasi sejauh mana Hutan Pendidikan Wanagama mampu menyediakan habitat yang mendukung kehidupan satwa liar.
2. Metode 2.1. Pengambilan data
Pengambilan data di lapangan dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2013 pukul 07.00 – 17.00 WIB. Penelitian dilakukan di petak 5, 6, 7, 13, 14, 16, dan 18 Hutan Pendidikan Wanagama I, Gunung Kidul, Yogyakarta.
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peta Wanagama I, GPS, tabung okuler, termohigrometer, protaktor, kompas, roll meter, alat tulis, buku identifikasi amfibi, dan tali. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu kodok buduk itu sendiri.
Metode yang digunakan untuk memperoleh data frekuensi kehadiran B. melanostictus yang terdapat di Hutan Pendidikan Wanagama I adalah metode line transect. Pengambilan data dilakukan pada 3 line. Line pertama berjarak 10 m dari sungai (sumber air), dan line berikutnya berjarak 50 m dari line
Gambar 1. Desain plot line transect
12
sebelumnya. Lebar line transect 20 m dan panjangnya 250 m yang kemudian dibagi menjadi 5 segmen dengan panjang 50 m.
Penutupan tajuk dan prnutupan tumbuhan bawah diestimasi menggunakan tabung okuler pada plot berbentuk lingkaran pada pusat tiap segmen (atau menyesuaikan kondisi di lapangan) dengan diameter 22,6 m dibuat enam titik pengamatan pada diameter lingkaran arah Utara-Selatan dan Timur-Barat, sehingga terdapat 15 titik. Penutupan tajuk dan penutupan tumbuhan bawah dihitung dengan menggunakan tabung okuler yang diberi benang/tali silang pada salah satu ujungnya. Pada setiap titik dilakukan pengamatan menggunakan tabung okuler ke arah atas untuk melihat penutupan tajuk dan ke arah bawah untuk penutupan tumbuhan bawah. Nilai dari penutupan tajuk dan tumbuhan bawah adalah persentase dari jumlah titik pengamatan yang penutupan tajuknya menyinggung titik persilangan benang dari tabung okuler.
50 m
50 m
20 m
20 m
20 m
50 m
50 m
10 m
Sungai
Untuk mengukur temperatur dan kelembaban yaitu dengan menggunakan alat Termohigrometer yang ditempatkan
pada plot lingkaran tiap-tiap segmen pada Line transect seperti halnya penempatan plot persen penutupan tajuk dan persen penutupan tumbuhan bawah, sehingga akan didapat 15 data temperatur dan kelembaban.
Data jarak sumber air dirancang seperti gambar 1, yaitu jarak dari sumber air pada line transect pertama adalah 10 m, line transect kedua 60 m, dan line transect ketiga 110 m. Dalam memperoleh data jarak terhadap pemukiman terhadap lokasi ditemukannya B. Melanostictus yaitu dengan menggunakan fasilitas Measuring Distance pada GPS.
2.2. Analisis data
Dalam menjawab tujuan yaitu mengetahui apakah Bufo melanostictus dapat dijadikan indikator lingkungan hutan di Wanagama yaitu harus diketahui terlebih dahulu ada tidaknya pengaruh karakteristik lingkungan hutan yang baik terhadap frekuensi kehadiran B. melanostictus. Untuk mengetahui pengaruhnyanya yaitu dengan menggunakan analisis regresi. Untuk mengetahui pengaruh karakteristik lingkungan dengan frekuensi kehadiran Bufo melanostictus yaitu dengan menggunakan analisis regresi. Sebelum dianalisis, data karakteristik lingkungan hutan dikategorikan terlebih dahulu yaitu ke kategori baik dan buruk. Menurut Abubakar (2009), persen penutupan tajuk yang menunjukan lingkungan hutan yang baik adalah diatas 50%, sebaliknya persen tumbuhan bawah yang menunjukkan lingkungan hutan yang baik adalah di bawah 50%. Sedangkan untuk kelembaban yang menunjukkan
Gambar 2. Desain penempatan plot lingkaran
13
lingkungan hutan yang baik didasarkan pada kelembaban yang disukai amfibi yaitu diatas 70% (Bredeer, 2009). Program komputer yang digunakan untuk menganalisis statistik yaitu R Program.
4. Hasil
Dari hasil pengambilan data di lapangan, frekuensi kehadiran B. melanostictus hampir tersebar di seluruh petak, hanya petak 6 dan 13 yang tidak ditemukan individu B. melanostictus. Berikut data frekuensi kehadiran B. melanostictus tersebut pada tiap petak di Wanagama:
Karakteristik lingkungan hutan
Wanagama dapat dilihat dari diagram berikut:
Petak Frekuensi Kehadiran
5 1
6 0
7 2
13 0
14 3
16 1
18 2
Tabel 1. Data frekuensi kehadiran Bufo melanostictus pada tiap petak di Wanagama
14
Untuk menguji regresi
karakteristik lingkungan hutan terhadap frekuensi kehadiran B. melanostictus dengan yaitu dengan mengkategorikan data lingkungan hutan yang baik itu dengan angka 1 dan yang buruk dengan angka 0. Data lingkungan hutan yang dikategorikan yaitu persentase penutupan tajuk, persentase penutupan tumbuhan bawah, dan kelembaban. Ho yaitu jika karakteristik lingkungan hutan yang baik itu berpengaruh negatif terhadap frekuensi kehadiran B. melanostictus. Sedangkan data yang lain seperti jarak dari sumber air, jarak dari pemukiman, serta temperatur disajikan sebagai data tambahan untuk mendapatkan gambaran tambahan karakteristik lingkungan hutan ditemukannya B. melanostictus. Berikut adalah data hasil uji regresinya:
keterangan: - kat.tajuk = Kategori persentase penutupan tajuk yang baik - kat.bwh = Kategori persentase penutupan tumbuhan bawah yang baik
- kat.lembab = Kategori kelembaban yang baik
5. Pembahasan
Bufo melanostictus ditemukan pada lingkungan hutan yang memiliki penutupan tajuk yang baik, penutupan tumbuhan bawah yang buruk, kelembaban yang buruk dan dekat dengan pemukiman manusia. Berdasarkan petak, B. melanostictus tersebut ditemukan di petak 5 dengan frekuensi kehadiran yaitu 1, di petak 7 yaitu 2, di petak 14 yaitu 3, di petak 16 yaitu 1, dan di petak 18 yaitu 2. Kodok tersebut tidak ditemukan di petak 6 dan petak 13. Jika dilihat dari jarak terhadap pemukiman manusia, kedua petak tersebut memiliki jarak yang paling jauh, hal ini dapat menajadi penyebab tidak ditemukannya B. melanostictus. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Maskey dkk, (2002) dan Kentwood, (2007) bahwa B. melanostictus sering terjadi kepadatannya lebih tinggi di habitat terganggu sekitar pemukiman manusia daripada di hutan yang tidak terganggu. Iskandar (1998) juga mengatakan bahwa habitat jenis ini selalu berada di dekat hunian manusia atau wilayah yang terganggu. Jenis ini tidak pernah terdapat di hutan hujan tropis.
Dalam menganalisis di statistik untuk mencari faktor lingkungan hutan yang berpengaruh terhadap frekuensi kehadiran B. melanostictus maka diperlukan data yang dapat menggambarkan karakteristik lingkungan hutan yang baik. Data yang dapat dikategorikan ke dalam kategori baik dan buruk yaitu penutupan tajuk, penutupan tumbuhan bawah dan kelembaban.
Coefficients: Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)(Intercept) 0.08618 0.06852 1.258 0.211kat.tajuk 0.01955 0.07085 0.276 0.783kat.bawah -0.09812 0.1288 -0.762 0.448kat.lembab -0.01092 0.0693 -0.158 0.875
15
Menurut Abubakar (2009), persen penutupan tajuk yang menunjukan lingkungan hutan yang baik adalah diatas 50%, sebaliknya persen tumbuhan bawah yang menunjukkan lingkungan hutan yang baik adalah di bawah 50%. Sedangkan untuk kelembaban yang menunjukkan lingkungan hutan yang baik didasarkan pada kelembaban yang disukai amfibi yaitu diatas 70% (Bredeer, 2009). Jika hasil uji regresi menunjukkan adanya pengaruh yang sesuai dengan teori, maka hipotesis diterima, jika hasilnya menunjukkan pengaruh yang tidak sesuai dengan teori atau tidak ada yang berpengaruh signifikan sama sekali maka hipotesis ditolak.
Dari hasil analisis statistik, tidak terbukti adanya pengaruh yang signifikan dari karakteristik lingkungan hutan yang baik terhadap frekuensi kehadiran B. melanostictus baik dari segi penutupan tajuk, penutupan tumbuhan bawah, maupun dari segi kelembaban ketiganya tidak ada yang nilai signifikansinya dibawah 0,05. Meskipun demikian, jika mengabaikan signifikansi maka adanya kesesuaian teori yaitu adanya pengaruh negatif dari penutupan tumbuhan bawah yang baik dan kelembaban yang baik, artinya semakin baik kondisi tutupan tumbuhan bawah dan kelembaban maka semakin jarang B. melanostictus. Namun hal ini tidak berlaku untuk penutupan tajuk, dari hasil terlihat bahwa penutupan tajuk yang baik berpengaruh positif terhadap frekuensi kehadiran B. melanostictus. Padahal berdasarkan hipotesis seharusnya penutupan tajuk berpengaruh negatif terhadap frekuensi kehadiran B. melanostictus, hal ini menunjukkan bahwa meskipun B. melanostictus lebih menyukai
kelembaban yang rendah dan penutupan tumbuhan bawah yang buruk bagi lingkungan hutan namun B. melanostictus masih membutuhkan penutupan tajuk yang tinggi, ini karena jenis tersebut meskipun memiliki asosiasi yang kuat terhadap kondisi lingkungan, namun sifat asli amfibi jika dilihat dari segi ekologinya yaitu membutuhkan tempat yang teduh dan tidak terkena cahaya matahari langsung untuk menjaga suhu tubuhnya sebagaimana jenis amfibi lainnya.
Lain halnya dengan jarak dari sember air dan temperatur, kedua faktor lingkungan ini tidak memiliki asosiasi yang kuat dengan kehadiran B. melanostictus. Dari data yang ada, jarak dari sumber air dan temperatur tidak mengindikasikan adanya hubungan dengan kehadiran B. melanostictus.
Dari paparan tersebut maka dapat dikatakan bahwa petak di Wanagama yang memiliki lingkungan hutan yang baik berdasarkan jarak dari pemukiman manusia yaitu petak 6 dan petak 13 dikernakan tidak ditemukan Bufo melanostictus pada kedua petak tersebut. Namun secara umum Bufo melanostictus belum dapat dijadikan sebagai indikator lingkungan hutan yang buruk karena tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari data karakteristik lingkungan yang telah ditentukan. Untuk membuktikan bahwa Bufo melanostictus dapat dijadikan indikator lingkungan hutan yang buruk maka diperlukan penelitian lanjutan yang lebih intensif agar dapat memperoleh data yang lebih representatif dengan kondisi yang sesungguhnya, diperlukan juga faktor lingkungan yang lain untuk dijadikan sebagai parameter yang
16
menunjukkan karakteristik lingkungan hutan.
6. Kesimpulan
Bufo melanostictus ditemukan pada lokasi yang persentase penutupan tumbuhan bawah yang buruk, kelembaban yang buruk, persentase penutupan tajuk yang baik, serta dekat dari pemukiman manusia. Frekuensi kehadiran Bufo melanostictus di Wanagama yaitu pada petak 5 = 1, petak 7 = 2, petak 14 = 3, petak 16 = 1, dan petak 18 = 2, dan tidak ditemukan di petak 6 dan petak 13 dapat disebabkan karena jauhnya titik pengamatan pada kedua petak tersebut dari pemukiman manusia. Bufo melanostictus belum dapat dijadikan indikator lingkungan hutan terhadap petak-petak di Hutan Pendidikan Wanagama.
Ucapan Terimakasih
Penelitian ini terlaksana karena adanya bimbingan dari semua dosen Laboratorium Satwa Liar Bagian Konservasi Sumberdaya Hutan Fakultas Kehutanan UGM serta dari co.ass praktikum ini. Tidak lupa rekan-rekan kelompok yang membantu dalam pembuatan proposal serta pengambilan data di lapangan.
Daftar Pustaka
Abubakar, F. 2009. Evaluasi Tingkat Keberhasilan Revegetasilahan Bekas Tambang Nikel Di PT. Inco Tbk. Sorowako, Sulawesi Selatan. Fakultas Kehutanan IPB. Bogor.
Ahmad, R. 1987. Lingkungan Sumberdaya Alam dan
Kependudukan Dalam Pembangunan. UI Press. Jakarta.
Alikodra, H. S. 2002. Pengelolaan Satwaliar. Yayasan Penerbit Fakultas Kehutanan. Bogor.
Anonim. 2009. Hutan Wanagama, Perpaduan Pemandangan Alam Nan Indah. Diakses tanggal 21 November 2013 dari http://gunungkidulonline.com/hutan-wanagama-perpaduan-pemandangan-alam-nan-indah/.
Badrus Z. dan Syafrudin. 2012. Pengelolaan Kualitas Lingkungan. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Diponegoro. Semarang.
Csurhes, S. 2010. Asian spined toad (Bufo melanostictus). Department of Employment, Economic Development, and Innovation. The State of Queensland.
Duellman WE and Heatwole H. 1998. Habitats and Adaptations. San Fransisco: Fog City Pr.
Fitri, A. 2002. Keanekaragaman Jenis Amphibi (Ordo Anura) di Kebun Raya Bogor. (Skripsi). Bogor: Fakultas Kehutanan IPB.
Heyer WR, Donnelly MA, McDiarmid RW, Hayek LC, Foster MS. 1994. Measuring and Monitoring Biological Diversity: Standard Methods for Amphibians. Smithsonian Institution Pr. Washington.
Iskandar, D. T. 1998. Amfibi Jawa dan Bali. Bogor: Puslitbang LIPI.
17
Kentwood, D. W. 2007. The Ecology & Behavior of Amphibians. The University of Chicago Press. Chicago and London.
Kristian B. 2011. Indian Toad (Duttaphrynus melanostictus). Diakses tanggal 28 November 2013 dari http://www.flickr.com/photos/kristianbell/5965192312/
Kusrini, M. D., dan Herman Remetwa. 2007. Pendugaan Asosiasi Interspesifik Dan Pengelompokan Tipe Habitat Beberapa Jenis Amfibi (Ordo : Anura Rafinesque, 1815). Diakses tanggal 22 November 2013 dari http://digilib.biologi.lipi.go.id/view.html?idm=31564
Kusrini, M. D. 2008. Pengenalan Herpetofauna. Bogor: Fakultas Kehutanan IPB.
Kusrini, M. D. 2009. Pedoman Penelitian dan Survei Amfibi. Bogor: Fakultas Kehutanan IPB.
Maskey, T., H. H. Schleich, and W. Kästle. 2002. Amphibians and reptiles of Nepal. Biology, Systematics, Field Guide. Ruggell. Gantner Verlag.
Mistar. 2008. Panduan Lapangan Amfibi & Reptil di Areal Mawas Propinsi Kalimantan Tengah (Catatan di Hutan Lindung Beratus). Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo The Borneo Orangutan Survival Foundation. Mawas.
Schneider, J. G. 1799. Historia Amphibiorum Naturalis et Literarariae. Fasciculus Primus. Continens Ranas, Calamitas, Bufones, Salamandras et Hydros in Genera et Species Descriptos Notisque suis Distinctos. Jena: Friederici Frommanni.
Stebbins RC and Cohen NW. 1997. A Natural History of Amphibians. New Jersey: Princeton Univ. Pr.