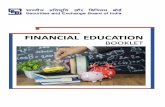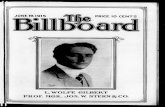Booklet Diskusi 100 Tahun Moch. Tauchid (1915-2015)
Transcript of Booklet Diskusi 100 Tahun Moch. Tauchid (1915-2015)
PERHIMPUNANPENDIDIKAN MASYARAKAT
Rabu, 18 Februari 2015 | Pukul 14.00 WIB
P2M | Jl. Wijayakusuma No. 17 Noyokerten, Sendang Tirto, Berbah, Sleman
MEM
BA
CA
KEM
BA
LIP
EM
IKIR
AN
AG
RA
RIA
MO
CH
. TA
UC
HID
DI
SK
US
I
Rubrik Pokok & Tokoh TEMPO No. 51/X, 14 Februari 1981, yang berisi berita meninggalnya Pak Tauchid pada usia 65 tahun. Moch. Tauchid adalah tokoh Taman Siswa dan merupakan salah satu tokoh reforma agraria. Mantan sekretaris Ki Hadjar Dewantoro ini juga dikenal sebagai salah satu pendiri BTI (Barisan Tani Indonesia), sebelum organ itu "dibajak" oleh PKI.
Imam Yudotomo | Moch. Tauchid dan Land-Reform
1
MOCH. TAUCHID DAN LAND-REFORM*
Oleh Imam Yudotomo
Rasanya, ayah termasuk satu dari sedikit orang-orang yang
sudah memikirkan nasib kaum tani sejak jaman pergerakan
kemerdekaan. Bisa dimengerti, karena ayah memang berasal dari
keluarga petani miskin. Dia ditinggal mati ayahnya ketika baru
berusia 11/2 tahun. Karena sawah yang ditinggalkannya sangat
kecil sehingga tidak bias menghidupi keluarganya, maka ibunya
menjadi bakul gendong, yang berjualam dari pasar yang satu ke
pasar yang lain manakala hari pasar tiba (pasaran). Hanya karena
kebaikan dan kebesaran hati pak guru yang di-ngenger-inya maka
dia bisa bersekolah, bisa masuk Normal-School, sekolah yang
mendidik guru sekolah desa. Sekolah ini setingkat dengan Sekolah
Guru Bawah (SBG), yang hanya setingkat dengan SMP. Dan bisa
dikatakan bahwa sebagian besar dari kehidupannya diabdikan
kepada perjuangan kaum tani.
Ayah mempunyai 2 pendapat yang dipercayai dan
diyakininya menjadi dasar dari perjuangannya bagi kaum tani di
Indonesia, yaitu:
1. Dalam pandangannya, kaum tani adalah kaum yang
sangat mulia dan sangat berjasa. Mereka memberi makan
seluruh umat manusia di dunia. Tetapi alih-alih diterima-
* Disampaikan dalam diskusi 100 tahun peringatan Moch. Tauchid, Perannya
Dalam Perjuangan Agraria, yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Pendidikan
Masyarakat (P2M) dan Rukun Tani Indonesia (RTI) di Jogjakarta, pada tanggal 18
Februari 2015.
Imam Yudotomo | Moch. Tauchid dan Land-Reform
2
kasihi, apalagi diberi penghargaan (rewards), kaum tani
malah ditindas dan dihinakan habis-habisan.
2. Dalam pandangannya, semua tanah-tanah perkebunan
asing yang ada di Indonesia semula adalah milik kaum
tani. Tanah-tanah itu berasal dari 20% tanah kaum tani
yang dirampas oleh VOC, dalam rangka tanam paksa
(cultuur-stelsel), yang dipakai untuk menanam
tanaman-tanaman yang laku di pasar Eropa. Oleh
pemerintah kolonial yang menggantikan VOC, melalui
Agrarische-wet yang diundangkan tahun 1870, tanah-
tanah tersebut lalu diberi status dan dikukuhkan sebagai
tanah erfpacht, dan diserahkan kepada kaum kapital
yang diundang ke Hindia Belanda. Setelah Indonesia
merdeka status tanah itu disebut dengan sebagai Hak
Guna Usaha (HGU). Dan karena Indonesia sudah
merdeka, maka dalam pandangan ayah, sudah
selayaknya dan bahkan seharusnya, tanah-tanah tersebut
dikembalikan lagi kepada pemiliknya semula, yaitu taum
tani. Karena itu, land-reform perlu dilaksanakan dan
merupakan keharusan untuk mengembalikan tanah-
tanah tersebut kepada rakyat.
Dalam pandangannya, ke-2 pendapat tersebut di atas
merupakan alasan mengapa kaum tani merasa mempunyai hak
yang syah untuk memperjuangkan kembali tanah-tanahnya. Kira-
kira sama dengan dengan kaum buruh ketika mereka faham
bahwa mereka punya hak yang syah untuk mendapatkan bagian
dari keuntungan yang didapat kaum capital, karena mereka
mengambil bagian yang vital dalam proses produksi yang
menghasilkan banyak keuntungan itu (surplus values).
Selain ke-2 pendapat yang sangat progresif-revolusioner
tersebut di atas, pikirannya tentang nasib kaum tani dirumuskan
Imam Yudotomo | Moch. Tauchid dan Land-Reform
3
dalam bukunya MASALAH AGRARIA, yang ditulis pada tahun
1953 ketika masih memimpin BTI. Oleh banyak orang, buku itu
dianggap sebagai mother-book atau buku-ibu dari buku-buku
tentang masalah agrria di Indonesia. Sebagian lagi menganggap isi
buku itu merupakan dasar dari Undang-undang Pokok Agraria
yang diundangkan di tahun 1960. Tetapi ayah tidak hanya
memikirkan nasib kaum tani akan tetapi juga melakukan sesuatu
tindakan yang nyata.
Ketika kemerdekaan diproklamirkan di tahun 1945, begitu
keluar dari penjara bersama kawan-kawan kiri yang lain
(Sardjono Petruk, Djadi Wirjosubroto) dia langsung mendirikan
BTI (Barisan Tani Indonesia). Dia ditangkap Jepang karena ikut
dalam gerakan di bawah tanah melawan Jepang yang dipimpin
Sjahrir dan Amir Sjarifudin. Akan tetapi ketika BTI direbut oleh
orang-orang PKI (tahun 1954), maka bersama-sama dengan 18
orang pimpinan BTI lainnya, dia menyatakan keluar dari BTI dan
mendirikan GTI (Gerakan Tani Indonesia).
Peristiwa ini terutama disebabkan karena adanya perbedaan
pandangan yang cukup tajam di antara keduanya, yaitu antara
BTI yang komunis dan GTI yang sosialis. Perbedaan itu terutama
dalam hal pandangan tentang hak milik atas tanah bagi kaum tani.
BTI yang komunis tidak menyetujui adanya hak milik atas tanah
bagi kaum tani. Dalam pandangan mereka, tanah adalah milik
negara dan negara yang mengatur penggunaannya. Di Rusia diatur
dengan sistem kolhoz, di Tiongkok diatur dalam komune rakyat.
Sedang di Vietnam diatur dalam sistem pertanian kolektif, yang
semua pengaturannya ditentukan oleh negara. Sedang GTI yang
sosialis menyetujui hak milik atas tanah bagi kaum tani dengan
menekankan pentingnya fungsi sosial dari tanah tersebut.
Sekalipun GTI belum merumuskan formula kepemilikan tanah
bagi kaum tani secara jelas dan detail, namun dari apa yang sudah
Imam Yudotomo | Moch. Tauchid dan Land-Reform
4
dilakukan, tampaknya formula GTI adalah memberikan hak atas
tanah sepenuhnya menjadi milik kaum tani, namun management
pemanfaatannya dilakukan secara bersama-sama dengan
kooperasi.
Apa yang dilakukan oleh anggota GTI sejak tahun 1952 di
desa Sukawangun, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten
Tasilmalaya, Jawa Barat, merupakan pelaksanaan dari formula
tersebut. Ketika mereka mengambil-alih perkebunan milik orang
Jerman di tahun 1957-an, mereka langsung membagi 750 hektar
tanah perkebunan tersebut menjadi 2 bagian, yaitu 450 hektar
dibagikan kepada rakyat yang tinggal di sekitar perkebunan itu
(redistribusi) dan 300 hektar lainnya dijadikan milik koperasi.
Koperasi Produksi Perkebunan Karet Wangunwati di
Tasikmalaya yang bisa disebut sebagai model redistribusi tanah
yang menjadi formula GTI yang sosialis itu sekarang masih ada dan
masih berfungsi dengan baik dan berhasil. Koperasi ini bahkan
berkembang, yaitu dengan menampung 200 petani karet yang lain
masuk menjadi anggotanya. Selain itu koperasi juga berhasil
membantu dan mengawal 500 petani yang dulu sama-sama
menerima redistribusi tanah mendapatkan sertifikat tanah hak
miliknya masing-masing (sertifikasi). Pernah ditetapkan sebagai
koperasi terbaik di Indonesia. Pada tahun 2014, koperasi ini bisa
mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebanyak Rp. 86.648.220,-.
Mampu mengexport karet olahan (smoked-sheet) 3.000 ton setiap
tahun, sekalipun tidak mengexport sendiri. Dan lebih dari itu,
pada tahun 2012 yang lalu koperasi ini mendapatkan perpanjangan
Hak Guna Usaha (HGU) untuk 35 tahun ke depan. Ketuanya (Sdr.
Endang As.) mendapat penghargaan Kalpataru pada tahun 2013.
Perlu juga ditambahkan bahwa dalam usaha membangun
koperasi tersebut ayah pernah diundang ke desa Sukawangun,
Tasikmalaya, tempat di mana koperasi itu berada, untuk
Imam Yudotomo | Moch. Tauchid dan Land-Reform
5
memberikan kursus mengenai perjuangan tani dan land-reform di
Indonesia. Sdr. Djadja Sudjana, sekretaris Koperasi Produksi
Perkebunan Karet Wangunwati, masih menyimpan makalah yang
ditulis ayah dan potret ayah kepunyaan ayahnya, bapak Sudjana,
yang waktu itu menjadi Ketua Cabang GTI Tasikmalaya.
Dari apa yang dikemuakan di atas, maka peran ayah dalam
perjuangan agrarian dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Dapat dikatakan bahwa melalui bukunya Masalah
Agraria ayah telah meletakkan dasar-dasar bagi land-
reform di Indonesia.
2. Bukan itu saja, ayah juga membangun kekuatan kaum
tani untuk memperjuangkannya, yaitu dengan ikut
mendirikan 2 organisasi tani yang besar, BTI dan
kemudian GTI, sekalipun kemudian ayah memilih ikut
GTI.
3. Dan lebih dari itu, ayah juga ikut melaksanakannya
dalam praktek. GTI yang dipimpinnya berhasil
mengambil alih perkebunan karet milik Jerman di Desa
Sukawangun dan membangunnya menjadi Koperasi
Perkebunan Karet Wangunwati sesuai dengan
formulanya.
Tidak mengherankan dan tidak berlebihan kalau kemudian
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) menetapkannya
medjadi Pelopor Perjuangan Agraria di Indonesia, bersama-sama
dengan Dr. Cipto Mangunkusumo, Mr. Iwa Kusumasumantri, Tan
Malaka, Bung Karno, Bung Hatta, Mr. Sadjarwo, Prof. Dr. Sayogo,
Dr. Gunawan Riyadi dan beberapa.lainnya (jumlahnya 16 orang).
Yogyakarta, 18 Februari, 2015
Mochammad Tauchid dan Filsafat Agraria Indonesia 1
MOCHAMMAD TAUCHID DAN FILSAFAT AGRARIA INDONESIA
Oleh M. Dawam Rahardjo
Lukisan jatidiri secara historis intelektual adalah salah satu
bentuk Kebenaran, karena ia ditulis sebagai ilmu pengetahuan. Dalam ajaran Basudewa Krisna, narator yang juga tokoh pelaku cerita dalam “Mahabharata”, ia merupakan satu dari lima sendi Kebenaran yang dijabarkan dalam keseluruhan epos itu.
Mochammad Tauchid (1915-1981), sebagaimana ditulis oleh Imam Yudotomo, pengarang buku “Mochammad Tauchid, Bapaku” telah diakui sebagai salah seorang tokoh pelaku sejarah dan Perintis Kemerdekaan oleh Negara RI. Tetapi rekaman sejarah tidak mencakup fakta historis mengenai salah seorang tokoh paling terkemuka “Partai Sosialis Indonesia” (PSI) bentukan Sutan Sjahrir dan Perguruan Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hadjar Dewantara (1889-1959). Selain itu, ia juga salah seorang pendiri “Barisan Tani Indonesaia” (BTI), yang kemudian menjadi underbouw Partai Komunis Indonesia (PKI) dan setelah itu ia keluar dari organisasi yang ia ikut bangun itu. Namanya ternyata tidak dijumpai dalam “Kamus Sejarah Indonesia” (2004, edisi bahasa Inggris; 2012, edisi bahasa Indonesia) terlengkap yang ditulis oleh dua sejarawan Indonesianis asal Amerika, Robert Cribb dan Audrey Kahin. Lebih mengherankan lagi, nama Mochammad Tauchid tidak pula dijumpai dalam entri “Ensiklopedia Umum” (1973) susunan A.G. Pringgodigdo, pengarang buku “Sejarah Pergerakan Rakyat”, dan Hassan Shadily yang juga cukup lengkap, tidak saja mengenai sejarah Indonesia, tetapi juga tentang gerakan Sosialis Indonesia. Dan lebih ironis lagi, nama itu juga tidak bisa didapati dalam buku “Ensiklopedi Indonesia” (1980) yang memuat informasi terlengkap mengenai sejarah Indonesia dari segala aspeknya. Bahkan nama itu tidak dijumpai dalam jaringan internet.
Mochammad Tauchid dan Filsafat Agraria Indonesia 2
Dengan demikian, maka Mochammad Tauchid telah mengalami ketidak-adilan serius dalam sejarah politik Indonesia. Tetapi ketidak-adilan itu telah berlangsung sangat lama hingga buku puteranya, Imam Yudotomo, yang mengenal bapaknya dengan baik itu terbit pada 2014.
Padahal, tahun 1952, ia telah menerbitkan buku masterpiece-nya “Masalah Agraria”, buku ilmiah tertebal yang pernah ditulis oleh para perintis bahkan seluruh pemimpin pergerakan nasional Indonesia hingga kini. Buku itupun mengalami cetak ulang beberapa kali dan terakhir pada tahun 2011 yang diterbitkan oleh Yayasan Bina Desa.
Sesungguhnya, jatidiri Mochammad Tauchid sudah terlukis dengan jelas dalam buku perintis ilmu pengetahuan Agraria Indonesia itu. Karena buku itu, bukan saja sekadar uraian mengenai pemikirannya yang bisa saja dianggap utopis, tetapi juga merupakan pengetahuan empiris yang ditulis secara sistematis. Pengetahuan itu, bukan pula hanya mengandung fakta-fakta sosiologis, politis, dan ekonomis, tetapi juga mengandung gagasan-gagasan besar, bahkan mengandung suatu gagasan filsafat agraria Indonesia yang menjadi pembuka bagi kajian-kajian ilmu agraria selanjutnya hingga sekarang dengan dipertahankannya kementeriaan yang mengelola agraria dalam pemerintahan hasil Pemilu 2014. Bahkan apa yang dipikirkan oleh Mochammad Tauchid itu, menjadi makin relevan lagi karena terjadinya konflik-konflik agaria yang menimbulkan banyak korban dan kerugian. Dalam pemikirannya, Mochammad Tauchid memperlihatkan jatidirinya sebagai seorang Sosialis Indonesia, yang disebut oleh Bung Karno sebagai “Marhenisme”. Dalam buku itu terbaca bahwa Mochammad Tauchid adalah seorang penjabar Marhenisme yang tidak ditulis oleh seorangpun, termasuk oleh Bung Karno sendiri sebagai penggagasnya. Maka dengan bukunya itu, Mochammad Tauchid adalah seorang ideolog Marhenisme yang seluk beluknya pernah ditulis oleh Imam Yudotomo itu. Tapi ia bukan hanya sekadar “man of ideas”, tetapi juga seorang “man of action” suatu kualitas yang jarang dimiliki oleh para tokoh pergerakan, kecuali Sukarno (1901-1970), Hatta (1902–1980) dan Sjahrir (1909- 1966), dan tentu saja Karl
Mochammad Tauchid dan Filsafat Agraria Indonesia 3
Marx (1818-1883) sendiri, Bapak Sosialisme Ilmiah, dalam pengertian Friedriech Engels (1820-1895).
Buku Mochammad Tauchid itu adalah sebuah interpretasi sosialisme ilmiah versi Indonesia yang menyadari bahwa Indonesia adalah sebuah negara agraris dan belum merupakan negara industrial. Karena itu maka Indonesia masih harus membangun sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian dan jikapun industri perlu dikembangkan, maka industri itu harus merupakan industri yang berbasis pertanian dan bukan mengolah bahan baku impor sebagaimana telah dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia sejak Orde Baru hingga sekarang. Dan pembangunan itu harus didahului dengan reformasi agraria sebagaimana telah dilakukan di Jepang dan Korea Selatan sebelum melakukan pembangunan pertaniannya.
Jika buku Mochammad Tauchid sendiri mengandung suatu sejarah makro mengenai gerakan tani Indonesia, maka buku Imam Yudotomo, yang telah menulis buku dan artikel mengenai Sosialisme Demokrasi dan Sosialisme Kerakyatan itu, adalah sebuah buku sejarah mikro yang menggambarkan jatidiri bapaknya yang ia kagumi itu. Sangat menarik keterangan Imam Yudotomo mengenai perbedaan pandangan politik antara Sutan Sjahrir dan Sumitro Djojohadikusumo yang lebih cenderung pada sosialisme negara dan sosialisme industrial itu. Pandangannya mengenai sosialisme agraris atau Marhenisme itu juga menggambarkan jatidiri Mochammad Tauchid yang dewasa ini harus direnungkan lagi dalam memahami strategi pembangunan yang harus diikuti dewasa ini.
Buku Imam Yudotomo ini sangat penting, karena ia bukan saja telah menyelamatkan nama tokoh pejuang besar yang terlupakan oleh bangsanya sendiri itu, tetapi juga memancing pemikiran kembali mengenai strategi pembangunan Indonesia dewasa ini. Dengan demikian, maka buku yang ditulis oleh seorang yang juga pelaku sejarah perjuangan sosialis—sejak masa mahasiswanya di Yogya dalam organisasi Gerakan Mahasiswa Sosialis (GMSOS)—adalah sebuah karya “Jas Merah”, singkatan dari frasa “Jangan Melupakan Sejarah”, sebagaimana dianjurkan oleh Bung Karno, sebuah anjuran untuk menegakkan keadilan
Mochammad Tauchid dan Filsafat Agraria Indonesia 4
sejarah yang dalam buku itu menyangkut tokoh Mochammad Tauchid.
Mochammad Tauchid sendiri sebenarnya adalah seorang penegak Kebenaran dan Keadilan di masa lampau dalam sejarah pergerakan Indonesia. Jatidirinya sebagai Penegak Kebenaran dan Keadilan itu dapat dijelaskan melalui “lima sendi Kebenaran” yang diajarkan oleh Basudewa Krisna dalam epos Mahabarata. Ajaran itu disampaikan oleh penjelmaan Dewa Wisnu sebagai manusia dan juga pelaku sejarah itu kepada “temanku” Drupadi, anak ketiga raja Drupada dari Kerajaan “Pancala”. Karena itu Drupadi disebut juga dengan nama Pancali.
Pada mulanya raja Drupada hanya punya seorang anak perempuan yang bernama Srikandi. Karena tidak memiliki seorang putera, maka ia mengangkat putrinya itu sebagai sebagai Panglima Perang. Ia dinilai ayahnya gagal menunaikan tugas, karena Srikandi pernah dikalahkan dalam perang tanding melawan Duryudana, walaupun Pangeran Hastinapura itu tetap tidak berhasil mengalahkan sang bapak. Drupada hanya bisa dikalahkan oleh Arjuna yang merupakan murid terbaik, teman, dan sekaligus seteru Guru Drona yang dulu pernah merebut kekuasaan darinya dan menjadikan wilayahnya jatuh ke tangan ras Arya yang melahirkan dinasti Kuru itu.
Drupada sangat merindukan dan memohon kepada dewa agar bisa memberikannya seorang putera. Dambaannya itu baru terkabul setelah ia melakukan upacara rajayatna yang menghasilkan seorang putra yang diberinya nama Justrajumena dan juga seorang puteri yang diberinya nama Drupadi. Keduanya diciptakan dari api suci. Setelah Justrajumena lahir, yang langsung menjadi seorang dewasa itu, maka putera yang bersumpah untuk mengabdi kepada cita-cita bapaknya itu langsung diangkat menjadi panglima perang menggantikan Srikandi yang tidak bisa berbuat apa-apa. Namun ia dibela oleh adiknya, Drupadi, yang percaya kepada kemampuan kakak perempuannya itu. Pembelaan Drupadi menimbulkan kemarahan bapaknya yang mengutuknya sebagai orang yang akan mengalami berbagai penderitaan dan bahkan mengusirnya dari kota kerajaan.
Mochammad Tauchid dan Filsafat Agraria Indonesia 5
Maka Drupadi, yang lahir langsung sebagai seorang puteri dewasa karena itu tidak punya pengalaman dalam hidup, harus keluar seorang diri tanpa pembimbing dan akhirnya sampai ke tepi sebuah jurang, melihat lembah yang luas terbentang. Dalam ketidaktahuan kemana ia harus pergi itu, tiba-tiba datang Basudewa Krisna yang menanyakan sedang apakah Drupadi di tepi jurang itu, seolah-olah ingin melakukan bunuh diri? Drupadi menjawab, bahwa ia sebenarnya sedang merenungkan jatidirinya yang terlahir dari api suci, tapi mengalami nasib malang diusir oleh bapaknya sendiri yang seharusnya memberikan kasih sayang dan bimbingan dalam menjalani hidup. Dengan menanyakan jatidirinya itu, ia sebenarnya sedang merenungkan dari mana asal-usulnya, apa tujuan hidupnya, dan bagaimana ia harus menjalani hidupnya itu. Dalam falsafah Jawa, ia sedang mencari “sangkan paraning dumadi” yang dengan kata lain, ia sedang mencari “agama”, kata lain dari Kebenaran yang harus dicari manusia.
Krisna yang arif bijaksana menjawab bahwa jatidiri itu hanya bisa dketahuinya jika ia mampu memahami apa itu Kebenaran. Ketika ia balik bertanya apa itu Kebenaran, maka Basudewa Krisna mengatakan bahwa Kebenaran harus dicari dalam perjalanan hidup yang mengandung sendi-sendi Kebenaran sebagai pegangan hidup. Kebenaran didukung oleh lima sendi. Pertama adalah pengetahuan. Kedua adalah cinta kasih. Ketiga adalah keadilan. Keempat adalah pengabdian. Dan kelima adalah kesabaran. Jadi, Kebenaran itu hanya bisa ditemukan dengan menjalankan kehidupan dan mencari makna dari lima sendi Kebenaran itu. Keseluruhan sendi Kebenaran itu terjalin dalam keseluruhan kisah Mahabharata yang dijelaskan tahap demi tahap oleh Krisna Basudewa sendiri, sejak ketika ia masih seorang dewa dan kemudian ketika ia menjelma menjadi manusia, sejak kelahiran hingga dewasanya, baik kepada Drupadi yang dipanggilnya sebagai “temanku” dan juga kepada para Pandawa putera Pandu dari kelahiran ibu Kunti, yaitu Yudistira, Bima dan Arjuna, demikian pula kepada Nakula dan Sadewa dari ibu Madra. Tapi penjelasan yang paling komprehensif dijelaskannya kepada Bisma Yang Agung, putera raja Sentanu dari Ibu Dewi Gangga.
Mochammad Tauchid dan Filsafat Agraria Indonesia 6
Dalam penjelasannya kepada Bisma yang Agung itu, Krisna menjelaskan kesalahan dan kelemahan Bisma. Penjelasan itu terjadi menjelang kematian Bisma dalam suatu analisis terhadap perjalanan Bisma yang tergambar sebagai “al Yaum al Hisab”, semacam Hari Perhitungan yang menimbang sikap dan perilaku manusia ketika hidup.
Dalam hari perhitungan yang terjadi pada hari ke sembilan perang Bharatayuda, Bisma—yang tidak mampu mengalahkan Krisna dengan senjata panahnya yang dahsyat dan telah menimbulkan banjir darah tetapi dilakukan dalam kondisi kejiwaan yang mati-rasa kemanusiaan itu—menjelaskan perbuatannya sebagai Panglima Perang yang melindungi Kerajaan Kuru, yang telah menjadi sumpahnya. Sikapnya yang membela kepada kemanusiaan itu dinilai oleh Krisna sebagai sikap egois yang optima prima. Tapi Bisma membantah bahwa ia bersikap egois, karena sejak awal ia sudah rela berkorban untuk tidak menjadi putera mahkota yang mewarisi kerajaan. Tetapi dijelaskan bahwa pengorbanan yang dianggap sebagai manifestasi kasih sayang kepada dinasti Kuru itu sebenarnya dilakukan dengan mengabaikan Keadilan. Dan ketika ditanya apa kelemahan dan kekeliruan Bisma itu, Krisna menjawab bahwa kelemahannya itu terkandung dari ketidaktahuan dirinya, yaitu ketidaktahuan tentang Kedilan. Padahal Keadilan itu terjalin dalam kehidupan yang selalu berubah. Karena itu wujud keadilan, yang memang suatu nilai yang tidak sederhana itu, juga mengalami perubahan. Sementara, karena sumpahnya yang tidak memahami makna kasih sayang sebagai nilai kemanusiaan, ia tidak mau berubah secara membabi-buta. Bisma, dengan menjalani apa yang dipahaminya sebagai pelaksanaan kewajiban, memang merupakan Kebaktian yang juga merupakan sendi Kebenaran. Dalam menjalankan kewajiban, ia juga telah menjalaninya dengan Kesabaran. Terutama kesabaran dalam membela dinasti Kuru yang telah melanggar prinsip Keadilan.
Pada hari perhitungan itu, Krisna menjelaskan bahwa pengabdian dan kesabaran Bisma dilakukan dengan kebungkamannya terhadap pelanggaran Keadilan dan kasih sayangnya yang juga melanggar Keadilan. Kesemunya itu
Mochammad Tauchid dan Filsafat Agraria Indonesia 7
dilakukannya karena ketidaktahuan Bisma mengenai Keadilan. Dalam ajaran Basudewa Krisna tersebut dikatakan bahwa
sendi Kebenaran pertama adalah pengetahuan, yakni pengetahuan mengenai Cinta, Keadilan, Kebaktian dan Kesabaran. Pengetahuan itulah yang mula pertama dibangun oleh Mochammad Tauchid mengenai masalah agraria. Pilihan itu bukan saja tepat, tetapi juga adil karena rakyat Indonesia itu telah memperoleh rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, berupa tanah yang subur, dimana “tongkat bisa menjadi tanaman”, tetapi di masa kolonial telah dijarah habis-habisan oleh penjajah asing. Menurut Mochammad Tauchid, Negara Indonesia Merdeka pertama-tama harus mengurus masalah agraria itu sebagai landasan bagi pembangunan pertanian, khususnya pertanian pangan yang menjadi sumber penghidupan rakyat Indonesia itu
Dalam buku Masalah Agraria, Mochammad Tauchid dalam kata pengantarnya membuat suatu “statement of truth” tentang tanah dan pertanian, dua interpretasi mengenai istilah agraria, yang menjadi landasan berfikirnya. Pertama ia mengatakan bahwa agraria adalah masalah pokok bagi penghidupan bangsa dan rakyat Indonesia. Masalah itu sudah menjadi persoalan umum dan persoalan masyarakat. Tidak saja menjadi persoalan, tetapi di sana-sini sudah menimbulkan kejadian-kejadian yang menyedihkan. Persoalan agraria adalah persoalan hidup rakyat Indonesia. Pernyataan kedua adalah bahwa politik penjajahan di Indonesia dapat digambarkan dengan politik agrarianya. Rakyat langsung merasakan akibat politik agraria kolonial Belanda berupa kemiskinan dan kesengsaraan. Statemen ketiga, sesudah lepas dari penjajahan, seharusnya Indonesia segera menyelesaikan lebih dahulu masalah agraria.
Ketiga statemen itu menunjukkan masalah Keadilan Sosial yang menimbulkan masalah kemiskinan dan kesengsaraan rakyat Indonesia sebagai akibat politik kolonial Belanda. Karena itu, respon pertama yang dilakukan oleh Negara Indonesia Merdeka adalah terlebih dahulu menyelesaikan masalah agraria yang diciptakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Tetapi sikap dan tindakan itu tidak dilakukan sesudah Indonesia Merdeka. Hal ini menurut Mochammad Tauchid adalah karena ketidaktahuan elit
Mochammad Tauchid dan Filsafat Agraria Indonesia 8
politik terhadap masalah agraria. Lebih lanjut, kondisi di atas disebabkan karena pengetahuan
mengenai politik agraria di Indonesia belum menjadi pengetahuan bagi umum. Tetapi pengetahuan itu baru dimiliki terutama oleh orang-orang yang akan mempergunakan politik bagi kepentingannya.
Dalam buku itu, seolah-olah Mochammad Tauchid adalah Basudewa Krisna yang sedang membuat perhitungan akhir atas perjalanan hidup Bisma dengan analisis bahwa ketidakadilan yang selama ini terjadi pada rakyat Indonesia adalah akibat dari ketidaktahuan mengenai Rahmat atau Cinta dan Keadilan.
Pengetahuan mengenai agraria menurut pendapatnya adalah persoalan yang meliputi seluruh penghidupan dan, karena itu, persoalannya tidak hanya terbatas kepada persoalan-persoalan hukum dan politik, tetapi juga soal-soal teknis yang menjadi persoalan bagi yang bersangkutan.
Dalam pernyataan tentang Kebenaran mengenai masalah agraria itu, Mochammad Tauchid tidak hanya berpendapat bahwa agraria hanya sekadar masalah hukum dan politik, tetapi juga masalah teknis. Karena itu maka Mochammad Tauchid menulis buku cetakan pertamanya pada tahun 1953—yang berarti lebih awal dari buku-buku Sumitro Djojohadikusumo, rekannya dalam PSI itu, walaupun tidak lebih awal dari pemikiran Sukarno, Hatta dan Syahrir. Pada tahun-tahun awal dasawarsa 1950-an, wacana tentang pembangunan ekonomi mulai ramai dibicarakan di ruang publik. Buku Mochammad Tauchid adalah pemicu diskusi masalah-masalah agraria, menuju UU Agraria tahun 1960 yang menjadi acuan dan sekaligus reforma agraria.
Situasi pertanahan itu bersumber dari pasal-pasal perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) yang berisikan pengakuan Belanda dan internasional atas kedaulatan RI di Kepuluan Nusantara. Perjanjian KMB juga berisikan ketentuan mengenai UNI Indonesia-Belanda yang memberikan ikatan untuk memulihkan kembali hak-hak ekonomi Belanda, termasuk pengembalian hak atas tanah kepada perusahaan-perusahan Belanda. Sementara itu, Mochammad Tauchid melihat sejumlah konflik agraria—berdasar blusukannya ke berbagai daerah seperti
Mochammad Tauchid dan Filsafat Agraria Indonesia 9
Tanjung Morawa, Sumatera Utara, pusat konflik tanah antara kaum tani melawan kaum kapital yang berusaha untuk mendapatkan kembali perkebunannya. Ia juga berkunjung ke daerah Priangan, yaitu Garut, Tasikmalaya, Bandung dan Sumedang, juga ke daerah Malang, Dampit, Turen, ke daerah Besuki, Jember, Lumajang dimana konflik tanah terjadi. Ia melakukan blusukan ke daerah konflik sebagai pimpinan BTI. Aksi-aksi perjuangan itu telah mengalami radikalisasi Marxis untuk melakukan pertanian kolektif seperti yang dilakukan di Rusia dan Cina. Tapi kecenderungan yang dianggap revolusioner itu, bagi Mochammad Tauchid merupakan gejala infantile atau kekanak-kanakan. Inilah yang membedakan Sosialisme Mochammad Tauchid dengan Sosialisme Marxis-Stalinis yang dibawakan oleh unsur-unsur PKI dalam BTI yang menyebabkan Mochammad Tauchid dan 18 orang yang sehaluan keluar dari BTI.
Mochammad Tauchid sebagai tokoh PSI-Marhenis tidak berjuang hanya berdasarkan ideologi Sosial-Demokrasi yang universal, tetapi juga secara kontekstual Indonesia. Ia mendasarkan teori ilmiah mengenai soal-soal agraria yang kompleks, namun tidak hanya berorientasi pada hukum Barat yang ditanamkan oleh kekuasaan kolonial Belanda, tetapi juga hukum Islam yang berlaku di Indonesia dan hukum adat yang bersumber dari budaya lokal. Kompleksitas permasalahan tanah itu harus dijelaskan secara ilmiah yang mencakup juga masalah-masalah teknis, karena harus diterapkan dalam rangka menuju reforma agraria tahun 1960, walaupun gagasan reforma agraria itu belum sepenuhnya dijalankan oleh Pemerintah Indonesia hingga sekarang ini sehingga konflik-konflik pertanahan seperti dulu masih juga terjadi, misalnya dalam kasus desa “Mesuji”, Lampung yang menelan banyak korban itu.
Di masa Orde Baru, diselenggarakan “Revolusi Hijau” yang menghasilkan peningkatan produksi pangan sehingga tercapai swasembada Beras tahun 1965 yang mendapatkan penghargaan dari FAO (Food and Agriculture Organization). Namun, dalam perspektif pemikiran Mochammad Tauchid, “revolusi” yang dijalankan atas perintah Negara itu, ternyata hasilnya tidak dinikmati oleh rakyat, tetapi dinikmati oleh pemilik modal asing
Mochammad Tauchid dan Filsafat Agraria Indonesia 10
dan Negara RI sendiri yang menjual sarana produksi pertanian dan jasa keuangan. Semua itu menggambarkan ketidakadilan dalam wujud kemiskinan dan kesengsaraan rakyat.
Mochammad Tauchid, dalam menegakkan Kebenaran, telah melakukan pengabdian yang diikutinya dengan kesabaran. Tapi tidak seperti halnya Bisma Yang Agung dalam kisah Mahabharata, ia sepenuhnya mengikuti ajaran Basudewa Krisna, walaupun ia tidak mengenalnya. Mochammad Tauchid adalah seorang anak kyai kampung, walaupun ia mengikuti ajaran Taman Siswa yang didasarkan pada budaya Jawa Kraton. Tapi, perjuangan yang ia lakukan sebenarnya adalah mengacu kepada budaya rakyat di lingkungan petani.
Dalam perspektif ajaran Krisna, Mochammad Tauchid telah berjuang mencari dan menegakkan Kebenaran dengan landasan pengetahuan mengenai agraria yang menyangkut peroalan tanah dan pertanian. Ia juga berorientasi kepada Cinta, tetapi bukan cinta yang buta dan sempit seperti yang dilakukan oleh Bisma Yang Agung, tetapi Cinta kepada tanah air dan bangsa. Ia juga berjuang menegakkan Keadilan Sosial yang mengacu kepada reforma agraria.
Imam Yudotomo, puteranya, tidak hanya mengagumi sang bapak yang jatidirinya telah ia tulis dalam rupa buku tetapi mengikuti gagasan bapaknya itu, walaupun dengan interpretasi baru. Ia ingin membebaskan petani dari penjajahan pupuk kimia yang di masa Orde Baru merupakan mekanisme eksploitasi atas tenaga petani demi kepentingan pemodal, baik asing maupun Negara. Ini dilakukannya dengan membimbing sekelompok mahasiswa yang berhaluan sosialis untuk melakukan pemberdayaan petani di Gunung Kidul dengan kegiatan budidaya yang disebut SRI atau”System of rice Intensification”. SRI adalah suatu interpretasi baru atas reforma agraria sebagaimana telah pernah diuji coba dalam bentuk lain oleh Gunawan Wiradi. Jika dosen senior IPB itu memperkenalkan sistem tumpangsari yang dilakukan oleh sebuah keluarga terdiri dari 5 orang anggota keluarga yang menggarap 2 hektar tanah yang bisa memberikan penghasilan optimal, maka Imam Yudotomo, dengan SRI-nya memberdayakan suatu kelompok petani yang memiliki lahan
Mochammad Tauchid dan Filsafat Agraria Indonesia 11
sekitar 100 hektar dengan pertanian organik, dengan pupuk urine sapi yang dibuat oleh kelompok tani sendiri untuk dipakai sendiri. Hasilnya adalah peningkatan produksi lahan terasering di lereng-lereng bukit dari 4 ton per hektar menjadi 10 ton dan kemudian 16 ton per hektar dalam tempo 2 tahun. Peningkatan produksi dan pendapatan petani itu dilakukan tanpa memperluas areal sawah yang membutuhkan anggaran besar itu. Apa yang dilakukan oleh Imam Yudotomo dan kawan-kawan mudanya itu adalah suatu bentuk atau interpretasi reforma agraria juga dengan mempergunakan teknologi tepat guna sehingga tanpa mempergunakan modal, kecuali modal sosial karena reforma agraria itu dilakukan secara gotong royong “rame ing gawe, sepi ing pamrih” yaitu kerja keras bersama tanpa kepentingan individu pemilik modal.
Generasi penerus sosialis kerakyatan pasca-PSI, dewasa ini mengelompok menjadi dua sayap. Sayap pertama, berpusat di Jakarta di bawah kepemimpinan Ir. Ibong Syahroezah, MPA, lulusan ITB dan Universitas Harvard. Ia putra Djohan Syahroezah, seorang tokoh sayap buruh dalam PSI. Kelompok ini mendirikan institut berbadan hukum koperasi dengan nama PIKIR, singkatan dari “Pusat Inovasi dan Kemandirian Indonesia Raya”. Kelompok ini lebih memperhatikan masalah perburuhan dalam perspektif koperasi dan masalah-masalah lingkungan hidup, yang disebut sebagai “sosialisme terapan”.
Kelompok kedua, berpusat di Yogyakarta, di bawah Imam Yudotomo sebagai mentornya. Berbeda dengan kelompok Jakarta, kelompok ini lebih mmperhatikan gerakan tani yang juga berwawasan lingkungan hidup, sebagaimana perkembangan Sosialisme Demokrasi yang menambah misi Sosialisme dengan wawasan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Nampak di situ bahwa Imam Yudotomo meneruskan perjuangan bapaknya dalam konteks abad 21. Imam Yudotomo yang kini sudah berusia 73 tahun dengan segala keterbatasannya itu masih terus berjuang dalam wawasan sosialisme agraris atau Marhenisme.
Jakarta, 20 November 2014
Sistematika Presentasi
1. Warisan pemikiran M. Tauchid
2. Belajar dari reforma agraria Wangunwati dan Ngandagan (from below)
3. Peluang pelaksanaan Reforma Agraria oleh pemerintah (from above)
Pokok Pikiran: Organisasi Tani• “Organisasi tani merupakan lapangan tani menyusun
kekuatan. Sebagai alat perjuangannya, untuk membebaskan dirinya dari penindasan politik, ekonomi dan sosial. Di sana belajar menambah kecerdasan otak dan jiwanya, dan dengan kesadarannya nanti membongkar segala pokok dan alat yang menjadi sumber kemiskinan dan kesengsaraan, untuk memperbaiki hidupnya”.
• Moch. Tauchid, Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia, (Yogyakarta: STPN dan Pewarta, 2009 [cetakan ke-tiga]), hlm. 394
• Melalui Gerakan Tani Indonesia yang didirikannya pada 17
September 1953, Moch. Tauchid semakin mengkerucutkan gagasan-
gagasan keberadaan organisasi tani sebagai wadah gerakan dan
pendidikan.
• GTI terlihat lebih berorientasi pendidikan kader. Rumusan-
rumusannya secara kompleks menempatkan ranah perjuangan
petani:
– sebagai produsen, golongan sosial, kelompok politik dan
ekonomi, dengan perjuangan perbaikan kehidupan tani melalui
cara produksi modern dan politik agraria yang membebaskan.
(daftar organisasi tani dipublikasi dalam Badan Usaha Penerbit Almanak Pertanian, Almanak Pertanian 1954, Jakarta, 1954. GTI bersekretariat di Jl. Merdeka No. 71, Bogor
• Kaum tani adalah warganegara (citizen), dengan segenap haknya. Pendidikan dan kursus kader (tingkat kabupaten hingga desa), dilakukan dalam upaya tidak hanya meningkatkan “keterampilan” bertani, namun penyadaran akan makna sebagai warganegara.
• Materi yang diusulkan dalam kursus kader di antaranya adalah: tatanegara, sejarah pergerakan nasional, ilmu jiwa dan masyarakat (sosiologi), pergerakan kaum tani, pergerakan buruh, ekonomi pertanian, hak atas tanah, kelaskaran, praktek kerja, dan juga pengetahuan tentang budidaya pertanian.
(Moch. Tauchid, “Mentjapai Kemakmoeran dengan Modernisasi Pertanian”, Barisan Tani Indonesia, 1947)
Pokok Pikiran: Lembaga Pendidikan sebagai Dunia Pemerdekaan
• Antara guru dan murid sama-sama menjadi warga belajar yang setara, guru tidak merasa lebih mengerti daripada muridnya. Tetapi murid tetap menaruh hormat dan penghargaan kepada sang guru. Sistem among inilah yang menjadi kebanggaan Taman Siswa.
• Kemerdekaan hanya dapat ditegakkan jika orang-orang telah memiliki jiwa yang merdeka.
• Orang-orang Taman Siswa adalah orang-orang merdeka yang tidak mau dipakai sebagai alat.Lembaga pendidikan adalah tempat dimana orang dapat menemukan jiwa merdeka dan merawat jiwa itu.
• Pendidikan harus dapat melepaskan orang dari perbudakan.
– 1. Perbudakan politik dimana orang hanya turut saja apa kata tuannya. Tidak ada lagi baginya Daulat Rakyat diganti dengan Daulat Tuanku.
– 2. Perbudakan ekonomi yang dijalankan dengan pemilikan atas tanah sebagai sumber dan gantungan hidup manusia. Apapun namanya, feodalisme atau kapitalisme, sama saja pemerasan atas rakyat.
– 3. Prbudakan sosial yang menempatkan rakyat dibawah kaki raja, bahkan di negara yang berdasar Pancasila ini.
Kritik terhadap arah pendidikan (1967) yang masih relevan:
• Tujuan orang menyekolahkan anaknya masih seperti dulu yaitu demi mendapatkan ijazah, diploma untuk menjadi pegawai yang dulu namanya priyayi.
• Keadaan itu menimbulkan adanya perdagangan diploma (ijazah) palsu dari perusahaan-perusahaan diploma gelap. Pembocoaran ujian dan pemalsuan ijazah berlaku terus menerus sejak pemerintah menyelenggarakan ujian negara. Orang manilai keadaan ini sebagai krisis moral dan akhlak anak didik padahal sumber masalahnya adalah politik penyelenggaraan pendidikan pemerintah.
• Terjadi intellectueele urbanisatie, yaitu kaum intelektual berkumpul di kota dan tak mau ke desa, meninggalkan desanya di belakang.
• Penggangguran yang membengkak yang timbul dari adanya pendidikan yang diarahkan untuk menjadi pekerja teknis tetapi tidak mampu menciptakan karya-karya baru dari kreatifitasnya. Sehingga semua lulusan bergantung pada ketersediaan kerja yang disediakan pemerintah.
Refroma Agraria Masa Lalu• Merdeka = Reforma Agraria. Reforma agraria sebagai
perjuangan pasca-kolonial.
• Di negara lain seperti Filipina bahkan reforma agraria dianggap hal yang mendasar sehingga dicantumkan dalam konstitusi, yakni Konstitusi 1987, yang kemudian diturunkan dalam UU Reforma Agraria dan Program Reforma Agraria nasional.
• Demikian pula Brazil melalui First Land Reform National Plan, Nikaragua dengan Konstitusi 1987, Afrika Selatan dalam Konstitusi 1996, dan Bolivia dalam Konstitusi 2009.
• UU No. 13 tahun 1946: penghapusan tanah-tanah perdikan
• UU No.13/1948 dan UU No.5/1950 penghapusan lembaga konversi, hak-hak konversi (kerajaan) dan hypotheek
• UU.No. 1/1958 penghapusan tanah patikelir dan hak-hak pertuanannya.
• UU No 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.
• Keseluruhan kebijakan di atas bermuara pada UUPA 1960 dan PP No. 224 Tahun 1961 mengenai Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian atau sering dikenal dengan Landreform.
• Ditetapkannya Obyek Landreform
– tanah negara yang diperoleh dari bekas hak erfpacht,
– bekas HGU,
– tanah kehutanan yang dikeluarkan dari kawasan,
– tanah bekas partikelir,
– tanah timbul,
–tanah terlantar (pasal 1 huruf d);
–tanah eks-swapraja (diktum keempat huruf A UUPA 1960);
–tanah hak milik pertanian yang melampaui batas maksimum (UU No. 56 Prp Tahun 1960);
– tanah milik abseente (Pasal 3 PP No. 224 Tahun 1961, Pasal 1 PP No. 41 Tahun 1964, dan Pasal 10 ayat 2 UUPA).
distribusi struktur agraria
sampai tahun 2009
tanah untuk pembangunan kota baru dan
pariwisata
tanah untuk pembangunan
perkebunan skala besar
tanah untuk proyek
pertambangan skala besar
tanah untuk proyek
kehutanan skala besar
tanah untuk industri berskala
besar
penyediaan tanah bagi aktivitas
pertanian rakyat
Masalah Agraria Sekarang: Persistensi Ketimpangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah
Pertama, Tanah kehutanan yang dikontrol oleh negara memiliki luas 147 hektar (74% total daratan Indonesia) pada tahun 1991 diberikan ijin konsesinya kepada 567 unit perusahaan (60,2 juta ha); pada 1999 kepada 420 unit (51,6 juta ha); pada 2005 kepada 258 unit (28 juta ha).
Kedua, Tanah untuk proyek pertambangan skala besar pada tahun 2009 luasnya hingga 264,7 juta hektar bagi 555 perusahaan pertambangan. Angka ini 1,5 kali lipat dari total daratan Indonesia karena terjadi tumpang tindih dari sebagian konsesi yang dibuka.
• Ketiga, tanah untuk pembangunan perkebunan skala besar pada tahun 1998 seluas 2,97 juta ha diperuntukkan bagi 1.338 perkebunan perusahaan swasta dan negara dengan 252 perkebunan yang ditelantarkan; pada tahun 2000 bertambah 3,52 juta ha; 770 ribu ha pada tahun 2005; dan sejak 2000 hingga 2012 tanah Indonesia yang ditanami sawit mencapai 10 juta ha.
• Keempat, tanah untuk pembangunan kota baru dan pariwisata yang pada tahun 1993 seluas 1,3 juta ha lahan diberikan ijin kepada 418 pengembang; 74.735 ha pada 1998; yang umumnya untuk perumahan, country club, dan lapangan golf. Pada tahun 2000-2007 dibangun 223 unit lapangan golf.
• Kelima, tanah untuk industri berskala besar. Pada tahun 1998 dibuka ijin kepada 46 perusahaan pengembang industri guna menguasai 17.470 ha tanah, sejumlah besar ditelantarkan.
Luas hak yang di dalamnya terdapat tanah terlantar (ha)
Tanah terindikasi terlantar (ha)
%
Hak Guna Usaha
2.253.685 1.729.775 76,8
Hak Guna Bangunan
176.480 146.248 82,9
Hak Pakai 423.361 401.704 94,9Hak Pengelolaan
788.809 538.304 68,4
Izin Lokasi 1.518.716 1.401.653 92,3Penggunaan Belum Optimal
3.168.606
Jumlah 7.386.290 BPN 2010
• Keenam, Indonesia memiliki lebih dari 28 juta rumah tangga petani (RTP) dengan rata-rata pemilikan tanah 0,36 hektar (Data BPS 2013).
• Terdapat 6,1 juta RTP di Jawa dan 5 juta di luar Jawa yang tidak memiliki tanah pertanian (tuna kisma).
• Sebanyak 32 juta jiwa petani Indonesia saat ini adalah buruh tani.
• meninggalkan tanah dan sawahnya.
• Laju penyusutan tanah pertanian mencapai angka 1,935 juta ha selama 15 tahun, atau rata-rata 129.000 ha/tahun (lebih 353 ha/hari tanah pertanian hilang). Setiap hari sebanyak 1.408 rumah tangga terpaksa kehilangan dan
Reforma Agraria Kontemporer
1. Janji Nawacita (Sembilan Agenda Prioritas)
– Menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah,
– Menyelesaikan sengketa tanah dan menentang kriminalisasi penuntutan kembali hak tanah masyarakat” (No. 4). Mendorong landreform dan program kepemilikan tanah 9 juta hektar” (No. 5),
– Mencetak 1 juta hektar lahan sawah baru di luar jawa” (No. 6) dalam rangka peningkatan produksi dan kemandirian pangan.
2. Pentingnya redistribusi kepada pemilik non-individual. Kepemilikannya dapat dalam bentuk tetapi kolektif seperti (koperasi) maupun komunal. Hal ini diperlukan agar pasca redistribusi yang disertai sertipikasi tanah secara individual kepada tuna kisma tidak terjadi peralihan hak dalam bentuk jual beli, sehingga berakibat pada pelepasan tanah.
Wangunwati dan Ngandagan memberi pengalaman ini
3. PP No 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar juga memiliki maksud sebagai pelaksanaan reform agraria.
– Akan tetapi banyak penetapan Tanah Terlantar digugat di pengadilan dan dimenangkan oleh perusahaan.
– Pemahaman bahwa TT belum bisa didayagunakan sebaba belum ada PP RA
4. Akses dan jaminan masyarakat terhadap tanah komunal desa perlu dipikirkan kembali seturut dengan lahirnya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
– Kewenangan kepala desa dalam melakukan penataan ulang atas penguasaan dan pemilikan tanah di desa perlu dipelajari lebih lanjut.
– Pengadaan tanah oleh desa dengan adanya dana desa hingga penguasaan serta penggunaannya untuk kepentingan masyarakat dan desa.
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga menyediakan peluang pelaksanaan reforma agraria (lihat pasal 29).
– Kebijakannya berupa pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
– penetapan lahan pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
– pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala BPN RI, Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-11/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, Nomor 8/SKB/X/2014, tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada dalam Kawasan Hutan, tertanggal 17 Oktober 2014, merupakan Forest tenure reform
• Perber tersebut kebijakan reforma agraria sebab membuka peluang bagi masyarakat dan berbagai pihak untuk mendapatkan hak atas tanah di kawasan hutan.
• BPN telah mengeluarkan 168 sertifikat hak komunal untuk masyarakat adat di Kalimantan Tengah agar tidak terjadi lagi perselisihan dengan pihak lain. (Detik Minggu, 01/02/2015 08:17 WIB , http://news.detik.com/read/2015/02/01/081738/2820197/10/menteri-agraria-keluarkan-hak-komunal-untuk-masyarakat-adat )
Apakah benar itu Reforma Agraria dan Betulkah Dilaksanakan?
Mari kita kawal terus Indonesia, melalui organisasi tani yang kuat dan dengan
pendidikan yang melahirkan individu-individu merdeka dan peduli!