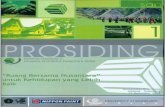Aulia Rahmat - Rekonstruksi Adat Minangkabau dalam ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Aulia Rahmat - Rekonstruksi Adat Minangkabau dalam ...
RAHMAT, Aulia
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU
DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA
OTONOMI DAERAH Kajian Terhadap Peraturan
Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 jo.
Perda Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok
Pemerintahan Nagari / penulis, Aulia Rahmat, -Cet.1.
-Magelang: PKBM “Ngudi Ilmu”, 2013.
xiv, 282 hlm, ; 16,5 x 24 cm
Bibliografi : hlm. 245
Indeks : hlm. 275
ISBN 978-602-1552-15-5
Pemeriksa Aksara: Maskur Rosyid
Rancang Sampul: A. Rahmat
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
All right reserved
Cetakan pertama, Oktober 2013
Penerbit:
PKBM “Ngudi Ilmu”
Jl. Kyai Sampir No. 05 Kalirejo
Salaman Magelang 56162
HP. 085714685441
Email : [email protected]
Irama Offset
Gd. Hijau, Jl. Kertamukti No. 190B
Ciputat Tangerang 15419
HP. 081280481098
Email: [email protected]
KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Allah, Tuhan Yang MahaEsa yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Selawat beserta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.
Penelitian ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ide awal penggarapan penelitian ini adalah makalah akhir dalam mata kuliah Law, Politics and Social
Changes yang diampu oleh Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar, M.S.P.D. Pada makalah akhir tersebut, penulis menganalisis realitas keharusan bisa baca tulis Alquran bagi siswa seluruh jenjang pendidikan dan calon pengantin di Kabupaten Solok. Secara historis, hubungan hukum Islam dengan hukum adat di Minangkabau telah bersinergi sejak terjadinya peristiwa Sumpah SatieBukik Marapalam. Pola ini kemudian mengalami dinamisasi yang tidak dapat dipisahkan dari kondisi dan kebutuhan politik pada setiap rezim pemerintahan. Fokus kajian tesis ini adalah rekonstruksi pemerintahan nagari kontemporer di Sumatera Barat serta pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberi dukungan baik materil maupun moril dalam menyelesaikan penelitian ini kepada: 1. Bapak Prof. Dr. Komaruddin Hidayat selaku Rektor UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta dan Prof. Dr. Azyumardi Azra selaku Direktur SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta beserta jajaran pimpinan, Prof. Suwito, M.A., Dr. Fuad Jabali, M.A., dan Dr. Yusuf Rahman, M.A. Juga kepada seluruh karyawan dan karyawati Tata Usaha dan Perpustakaan SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
2. Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar, M.S.P.D., selaku pembimbing dan promotor penulisan tesis ini. Sentilan-sentilan dan kritikan beliau sangat bermanfaat dalam membentuk kebiasaan dan pola pikir penulis dalam perkembangan akademis ke depan. Ucapan terima kasih dan
iv | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
penghormatan penulis juga kepada seluruh jajaran Dosen SPs UIN Syarif Hidayatullah yang tidak mungkin disebutkan satu persatu;
3. Orang-orang yang sangat berarti dalam kehidupan Penulis, Ayahanda tercinta Drs. Ahmad Saiyadi Syarif dan Ibunda tersayang Dra. Hasnetti. Tidak terlupakan juga Kakek Penulis Alm. Hasan Basri Tamin dan Nenek Penulis Tinur Sirin. Demikian juga dengan dorongan semangat yang Penulis dapatkan dari penerus masa depan keluarga, Adinda Fadhly A.S., S.S., Kahirat A.S., S.Ked. dan Muhammad Hafizh A.S. Pemberi inspirasi dan penjaga asa penulis, teristimewa kepada Sani Nofita, A. Md. Tidak terlupakan juga kepada Alfa Syukri (mak Uncu), Novita Dewi (mintuo) dan si kecil M. Aryan Defa yang telah memberikan ruang untuk berteduh dan kepercayaan kepada penulis untuk menimba ilmu dan mencari pengalaman selama di negeri orang.
4. Presidium Solok Saiyo Sakato (S3), Bapak Irjen Pol (Purn) Drs. H. Marwan Paris, M.B.A. Dt. Maruhun Saripado, Bapak H. Firdaus Oemar Dt. Marajo dan Bapak Muchlis Hamid, M.B.A. Rajo Dewan yang memberikan ruang bagi penulis untuk ikut menyaksikan dan terlibat langsung dalam Musyawarah Adat 2012 serta memberikan kesempatan bagi penulis untuk ikut serta berdiskusi dengan tokoh adat dan tokoh nasional yang terlibat di dalamnya. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Hj. Yefni Delfitri, S.H., M.H. selaku Ketua Ikatan Keluarga Perantau Muaropaneh (IKPM) se-Indonesia;
5. Buat rekan-rekan seperjuangan angkatan 2010 yang telah menanamkan sifat keberanian dan mengajarkan indahnya bersatu dalam rasa kebersamaan, Adzan, Zamzam, Ghufron, Devrian, Jenet, Ami, Rifa, Ayu, Rifqy, Mbak Ani dan banyak lagi dan tidak mungkin disebutkan satu persatu. Teristimewa buat teman-teman Marawa Community, Arsyad, Aidil, Defel, Khairu Syukri, Furqon, Ismail, Fahrul, Aprianif, Andi dan Razes, semoga budaya saling berbagi ilmu tetap terjaga di antara kita semua. Tidak terlupakan juga teman-teman senasib dan seprofesi di IKPM Jabodetabek, Debi (mandan #52), Donal Fariz, da Am, da Nopa, da Nopi, Adang, Andi dan masih banyak lagi yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.
KATA PENGANTAR | v
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Akhirnya setangkai doa penulis mohonkan untuk semua pihak yang telah berpartisipasi, semoga Allah SWT. memberikan balasan yang layak atas partisipasi bantuan dan kerja samanya serta menjadi amal saleh hendaknya. Harapan Penulis, semoga karya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi penulis sendiri. Amin ya Rabb.
Ciputat, 15 Juli 2013
Aulia Rahmat
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR -- iii DAFTAR ISI – vii DAFTAR MATRIKS - ix DAFTAR TABEL -- ix DAFTAR GRAFIK -- x DAFTAR BAGAN -- xii PEDOMAN TRANSLITERASI -- xv BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah -- 1 B. Masalah --12
1. Identifikasi Masalah -- 12 2. Rumusan Masalah -- 12 3. Batasan Masalah -- 13
C. Tujuan Penelitian -- 13 D. Signifikasi Penelitian -- 13 E. Literature Review -- 14
F. Metodologi Penelitian -- 21 1. Paradigma Penelitian dan Metode Pendekatan -- 21 2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data -- 22 3. Metode Analisis -- 23
G. Sistematika Penulisan -- 23
BAB II RELASI ADAT DAN ISLAM DI MINANGKABAU A. Masa Pra Kolonialisme -- 27
1. Periode Minangkabau Timur -- 27 2. Kerajaan Pagaruyung -- 32
B. Masa Kolonialisme -- 38 1. Awal Kedatangan Bangsa Asing -- 38 2. Gerakan dan Revolusi Paderi -- 47 3. Pendudukan Jepang -- 57
C. Masa Kemerdekaan Hingga Reformasi -- 65
viii | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
BAB III IDENTITAS SOSIAL DALAM DEMOKRATISASI PEMERINTAHAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA
A. Identitas Sosial Masyarakat Minangkabau -- 79 B. Desentralisasi Kekuasaan dan Kebijakan Otonomi
Daerah -- 83 1. Masa Kolonialisme -- 90 2. Era Demokrasi Parlementer -- 95 3. Era Demokrasi Terpimpin -- 103 4. Era Orde Baru – 107 5. Era Reformasi Hingga Saat Ini -- 109
BAB IV FORMALISASI NILAI ADAT MINANGKABAU DALAM
BENTUK SISTEM PEMERINTAHAN NAGARI A. Formalisasi Nilai Adat Tradsional Minangkabau -- 117 B. Eksistensi Nagari -- 152 C. Sistem Pemerintahan dan Peran lembaga Adat dalam
Nagari -- 162 D. Finansial dan Hak Ulayat Nagari -- 168
BAB V DAMPAK PENERAPAN NILAI ADAT DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NAGARI MINANGKABAU
TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
A. Pemekaran Wilayah dan Pelayanan Publik -- 177 1. Bidang Pendidikan -- 191 2. Bidang Kesehatan -- 203 3. Bidang Infrastruktur Perhubungan Dasar -- 206 4. Bidang Daya Saing Daerah -- 210
B. Kesejahteraan Masyarakat -- 212 C. Penyelesaian Konflik dan Sengketa -- 227 D. Partisipasi Tokoh Adat dalam Pembangunan -- 234
BAB VI PENUTUP A. Kesimpulan -- 241 B. Saran -- 244
DAFTAR KEPUSTAKAAN -- 245 GLOSARIUM -- 269 SINGKATAN DAN AKRONIM -- 273 INDEKS – 275 TENTANG PENULIS -- 279
DAFTAR MATRIKS
Matriks 4.1. Perkembangan Pemerintahan Nagari dan Penguasaan
Ulayat Nagari Di Sumatera Barat Sejak kemerdekaan
Hingga Reformasi -- 174
DAFTAR TABEL
Tabel 5.1. Perbandingan Jumlah Unit Pemerintahan di Sumatera
Barat Era Pemerintahan Desa dan Nagari Tahun 1998 dan
2011 -- 181
Tabel 5.2. Perkembangan Unit Pemerintahan Di Sumatera Barat
Tahun 2009 – 2011 -- 184
Tabel 5.3. Distribusi Unit Pemerintahan Di Sumatera Barat Tahun
2011 -- 185
Tabel 5.4. Distribusi Jumlah Nagari per Kecamatan Di Sumatera
Barat Tahun 2011 -- 188
Tabel 5.5. Jumlah Sekolah Di Sumatera Barat Tahun 2007 – 2011 --
193
Tabel 5.6. Jumlah Murid Di Sumatera Barat Tahun 2007 – 2011 --
193
Tabel 5.7. Jumlah Guru Di Sumatera Barat Tahun 2007 – 2011 --
194
Tabel 5.8. Persebaran Variabel IPM Menurut Kabupaten/Kota di
Sumatera Barat Tahun 2011 -- 222
x │AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
DAFTAR GRAFIK
Grafik 5.1. Perkembangan Unit Pemerintahan Terendah di Sumatera
Barat Berdasarkan Era Pemerintahan -- 180
Grafik 5.2. Kepadatan Penduduk di Sumatera Barat Tahun 2011
(dalam jiwa/km2) -- 187
Grafik 5.3. Perkembangan Realisasi Pendapatan dan Belanja Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2007 – 2012 -- 190
Grafik 5.4. Perkembangan Realisasi Belanja Bidang Pendidikan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 – 2012 -- 191
Grafik 5.5. Perkembangan Persentase Realisasi Belanja Bidang
Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 – 2012 --
192
Grafik 5.6. Perkembangan Rasio Murid per Sekolah Di Sumatera
Barat Tahun 2007 – 2011 -- 195
Grafik 5.7. Perkembangan Rasio Guru per Sekolah di Sumatera Barat
Tahun 2007 – 2011 -- 196
Grafik 5.8. Perkembangan Rasio Murid per Guru di Sumatera Barat
Tahun 2007 – 2011 -- 197
Grafik. 5.9. Perkembangan Presentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke
Atas Menurut Partisipasi Sekolah di Sumatera Barat
Tahun 2007 – 2011 -- 198
Grafik 5.10. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2003 – 2012 (dalam %) -- 200
Grafik 5.11. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2003 – 2012 (dalam %) -- 201
Grafik 5.12. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2003 – 2012 (dalam %) -- 202
DAFTAR MATRIKS, TABEL, GRAFIK, DAN BAGAN │xi
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Grafik 5.13. Perkembangan Realisasi Belanja Bidang Kesehatan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 – 2012 -- 203
Grafik 5.14. Perkembangan Persentase Realisasi Belanja Bidang
Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 – 2012 --
204
Grafik 5.15. Proporsi Kelahiran Berdasarkan Penolongnya di Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2011 -- 205
Grafik 5.16. Perkembangan Angka Kematian Bayi Provinsi Sumatera
Barat Tahun 1971 – 2010 (dalam per 1000 kelahiran) --
206
Grafik 5.17. Perkembangan Panjang dan Kondisi Jalan di Sumatera
Barat Tahun 2007 – 2011 -- 207
Grafik 5.18. Perkembangan Ruas Jalan Di Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2008 – 2011 (dalam kilometer) -- 208
Grafik 5.19. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2004 – 2011 (dalam
Rupiah) -- 210
Grafik 5.20. Perkembangan Persentase Peningkatan PDRB Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2005 – 2011 (dalam %) -- 211
Grafik 5.21. Pemanfaatan Tanah Sebagai Kawasan Lindung &
Budidaya Di Sumatera Barat Tahun 2012 (dalam km2) –
213
Grafik 5.22. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas Yang Bekerja
Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Sumatera Barat
Tahun 2009 – 2012 -- 214
Grafik 5.23. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2008 – 2012 (dalam 1.000 jiwa) --
217
xii │AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Grafik 5.24. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2007 – 2012 (dalam persen) -- 218
Grafik 5.25. Perkembangan Garis Kemiskinan di Sumatera Barat
Tahun 2007 – 2012 (dalam Rupiah) -- 219
Grafik 5.26. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Provinsi Sumatera Barat & Indonesia Tahun 1996 – 2011
– 220
Grafik 5.27. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009 – 2011 -- 223
Grafik 5.28. Perbandingan Rata-rata Variabel IPM Antara Kabupaten
dengan Kotamadya di Sumatera Barat Tahun 2012 -- 224
Grafik 5.29. Perkembangan Angka Tindak Pidana di Sumatera Barat
Tahun 2003 – 2011 -- 233
DAFTAR BAGAN
Bagan 5.1. Model Transformasi Bentuk Pemerintahan Terendah di
Sumatera Barat – 183
Pedoman Transliterasi
b = ب
t = ت
th = ث
j = ج
h{ = ح
kh = خ
d = د
dh = ذ
r = ر
z = ز
s = س
sh = ش
s{ = ص
d{ = ض
t{ = ط
z{ = ظ
ع = ‘
gh = غ
f = ف
q = ق
k = ك
l = ل
m = م
n = ن
h = ه
w = و
y = ي
Short: a = ´ ; i = ِ ; u = ُ
Long: a< = ا ; i> = ي ; ū = و
Diphthong: ay = ا ي ; aw = ا و
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kebijakan desentralisasi sudah dikembangkan di Indonesia sejak tahun 1999, pasca lengsernya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia.1 Reformasi hukum merupakan salah satu amanat penting dalam rangka pelaksanaan agenda reformasi nasional. Reformasi hukum mencakup agenda penataan kembali berbagai institusi hukum dan politik2 mulai tingkat pusat sampai tingkat pemerintahan daerah terendah. Pengesahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah3 merupakan tanggapan dan jawaban4 Pemerintah terhadap desakan demokratisasi dan pembaharuan sistem hukum Indonesia sejak reformasi mulai digulirkan pada tahun 1998.5 Pembaharuan format
1 Provinsi Sumatera Barat merupakan provinsi yang pertama kali menanggapi hal ini dengan melakukan restrukturisasi administrasi pemerintahan. Franz and Keebet von Benda-Beckmann. “Recentralization And Decentralization in West Sumatera”, dalam Decentralization and Regional Autonomy in Indonesia: Implementation and
Challenges, eds. Coen J.G. Holtzappel dan Martin Ramstedt (Leiden: International Institute for Asian Studies, 2009), 293. Hal ini dapat dilihat dengan kemunculan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari yang kemudian disusul dengan kemunculan beberapa Perda pada tingkat Kabupaten/Kota yang memuat nilai-nilai syariah.
2 Utang Rosidin, Otonomi Daerah dan Desentralisasi (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 9. Arah pembangunan sistem hukum nasional harus diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan hukum yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan hukum sebagaimana yang terdapat dalam RPJMN 2004-2009.
3 Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, asas pemerintahan yang dipakai adalah asas desentralisasi dengan memperkuat fungsi DPRD dalam pembuatan Peraturan Daerah. Akan tetapi kaum reformis dan pakar otonomi daerah memandang bahwa regulasi ini mempunyai kelemahan yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan reformasi, maka diajukan usulan untuk direvisi. Oleh sebab itu, muncullah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai koreksi total terhadap regulasi sebelumnya. Muntoha, “Otonomi Daerah dan Peraturan-peraturan Daerah Bernuansa Syariah”, Jurnal Hukum, Nomor 2 Volume 15 (2008) : 261.
4 Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah (Yogyakarta: ANDI, 2004), 4.
5 Muhammad Fadhly Ase, Mengkaji Ulang Perda Bermuatan Syari’ah: Sebuah
Pendekatan Yuridis Normatif. Penulis adalah hakim pada Pengadilan Agama Kisaran. Sesuai dengan semangat reformasi yang terjadi pada tahun 1998, format
2 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
pemerintahan idealnya juga akan mempengaruhi sistem dan administrasi yang mendorong tetap berjalannya sistem pemerintahan.
Perubahan tersebut menimbulkan beberapa pergeseran signifikan dalam sistem pemerintahan.6 Perubahan yang mendasar terlihat pada hubungan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif daerah. Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, hubungan antara eksekutif dan legislatif di daerah tidak mencerminkan hubungan kemitraan yang sejajar.7 Bahkan secara sederhana dapat dikatakan bahwa badan legislatif di daerah (DPRD) berada satu tingkat di bawah kekuasaan eksekutif daerah. Ketidaksetaraan ini pada akhirnya membuat tidak berjalannya mekanisme checks and balances sebagaimana mestinya.
Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan yang sebelumnya tersentralisir pada pemerintah pusat.8 Dalam proses desentralisasi,9 kekuasaan pemerintah pusat dialihkan ke Pemerintah Daerah sebagaimana mestinya sehingga
penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia juga mengalami perubahan dari pendulum sentralisasi ke pendulum desentralisasi. Hal ini dapat dianalisis dari format pembagian kewenangan yang berpola residu dan peletakkan lokus otonomi daerah pada tingkat kabupaten/kota. Hal ini dianut secara tajam di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Kondisi ini mengalami pergeseran kembali di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Berbagai kewenangan yang semula dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi diserahkan kepada daerah kabupaten/kota. Eko Prasojo, Desentralisasi: Dampak Perubahan Yang Diperlukan, sebagaimana yang dimuat dalam http://www.forplid.net/modul/134-desentralisasi-dampak-perubahan-yang-diperlukan-.html, akses tanggal 29 September 2011, 12:32 WIB. Lihat juga dalam B. N. Marbus, Otonomi Daerah 1945-2005: Proses dan Realita Perkembangan Otda Sejak Zaman Kolonial Sampai Saat Ini (Jakarta: 2005, Pustaka Sinar Harapan), 101.
6 Sebelum tahun 1999, pemerintah daerah hanya diberikan otonomi pada kepentingan internalnya saja. Coen J.G. Holtzappel, “Introduction: The Regional Governance Reform in Indonesia, 1999-2004”, dalam Decentralization and Regional
Autonomy in Indonesia: Implementation and Challenges, eds. Coen J.G. Holtzappel dan Martin Ramstedt (Leiden: International Institute for Asian Studies, 2009), 1.
7 Deddy Ismatullah, “Kata Pengantar”, Otonomi Daerah dan Desentralisasi, ed. Utang Rosidin (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 10.
8 Penjelasan lebih lanjut bisa disimak dalam Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan
Konstsitualisme Indonesia (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 218-219. 9 Desentralisasi adalah sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang
menyangkut pola hubungan antara pemerintahan nasional dan pemerintahan lokal. Syaukani H.R., dkk., Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), xvii. Mekanisme yang diterapkan adalah pemerintahan nasional melimpahkan kewenangan kepada pemerintah daerah dengan aspirasi masyarakat setempat yang diselenggarakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Utang Rosidin, Otonomi Daerah, 134.
PENDAHULUAN | 3
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah. Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi ini dinilai sangat penting, terutama untuk menjamin agar proses integrasi dapat dipelihara dengan sebaik-baiknya.10 Hal ini dapat dimaklumi karena Bangsa dan Negara Indonesia merupakan negara yang multikultural dan terdiri dari berbagai etnis dan suku bangsa.11 Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi kewenangan tidak hanya menyangkut pengalihan kewenangan dari atas ke bawah,12 tetapi juga perlu diwujudkan atas dasar prakarsa dari bawah untuk mendorong tumbuhnya kemandirian pemerintahan daerah sebagai faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan otonomi daerah.
Lebih jauh lagi, kebijakan otonomi daerah itu tidak hanya dilihat sebagai agenda perpindahan kewenangan dari pusat ke daerah, namun lebih dari itu adalah menyangkut pemindahan kewenangan dari pemerintah kepada masyarakat.13 Pandangan inilah yang menjadi nilai dasar dari kebijakan otonomi daerah itu sendiri. Otonomi daerah merupakan kewenangan untuk membuat kebijakan (mengatur) dan melaksanakan kebijakan (mengurus) berdasarkan perkara sendiri, sehingga masyarakat yang berada pada satu teritori tertentu adalah pemilik dan subjek otonomi daerah.14 Hal ini, membawa konsekuensi akan perlunya partisipasi aktif dari masyarakat dalam setiap tahap penyelenggaraan otonomi. Keberadaan otonomi daerah ini berarti
10 Utang Rosidin, Otonomi Daerah, 44. 11 Dalam kultur masyarakat Indonesia yang paternalistik, kebijakan
desentralisasi dan otonomi daerah tidak akan berhasil apabila tidak dibarengi dengan upaya sadar untuk membangun keprakarsaan dan kemandirian daerah sendiri. Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusialime, 278. Otonomi daerah merupakan sesuatu hal yang lazim sebagai asas dalam penyelenggaraan pemerintahan sejak munculnya kesadaran di kalangan pengelola negara bahwa tidak semua urusan pemerintah dapat diselesaikan secara sentralisasi. Mengingat kondisi geografis, kompleksitas perkembangan masyarakat, kemajemukan struktur sosial dan budaya lokal serta adanya tuntutan demokratisasi dalam dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jazuli Juwaini, Otonomi Sepenuh Hati: Pokok-pokok Pikiran Untuk Perbaikan Implementasi Otonomi
Daerah (Jakarta: al-I’tishom, 2007), 7. 12 Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan akan lebih
mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. H.A.W. Widjaya, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 7.
13 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, 219. 14 Marzuki Alie, “Kebijakan Desentralisasi Dalam Membangun Kualitas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Era Globalisasi”, Makalah ini disampaikan pada Seminar Nasional Forum Komunikasi dan Kerjasama Mahasiswa Ilmu Pemerintahan se-Indonesia (FOKERMAPI) di Universitas Tadulako Palu Sulawesi Tengah, 06 Oktober 2010.
4 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
penyerahan kewenangan kepada masyarakat di daerah agar terus tumbuh dan berkembang sendiri dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Tujuan utama dari kondisi ini adalah adanya pembangunan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan.
Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.15 Hubungan antara daerah otonom dengan pemerintah pusat merupakan hubungan antarorganisasi, bukan hubungan intraorganisasi. Sedangkan hubungan antarsesama daerah otonom adalah hubungan yang setara, tidak hierarkis.16 Pergeseran kewenangan sebagaimana yang telah disinggung di atas, pada dasarnya memberikan alasan pendorong bagi masing-masing pemerintah daerah untuk mandiri tanpa ada intervensi dari pemerintah pusat.
Untuk mewujudkan kepentingan daerah yang didasarkan pada aspirasi masyarakat, pemerintahan daerah diberi tanggung jawab besar dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk kepentingan masyarakat daerahnya sendiri. Kewenangan membuat peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah. Sebaliknya, peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah.17 Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan asas keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.18 Hal ini merupakan konsekuensi logis penerapan konsep otonomi daerah dan desentralisasi kewenangan yang menjadi salah satu bentuk pembaharuan pada era reformasi.
Dalam masa demokratisasi berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara di era reformasi ini, sektor pembangunan hukum mutlak membutuhkan pembenahan secara integral baik dari segi penegakan hukum yang responsif tehadap dinamika dan kebutuhan hukum, juga
15 Rian Nugroho Dwidjowijoto, Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa
Revolusi (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), 46. Penjelasan mengenai hal ini juga diulas secara rinci dalam Wakidul Kohar, “Komunikasi Antarbudaya di Era Otonomi Daerah” (Disertasi Doktoral UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), 1.
16 H.A.W. Widjaya, Otonomi Daerah, 93. 17 Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala
Daerah Secara Langsung (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 131. 18 H.A.W. Widjaya, Otonomi Daerah, 23.
PENDAHULUAN | 5
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
dalam proses pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat secara nasional.19 Pasca kelahiran regulasi yang berkaitan dengan otonomi daerah dan desentralisasi kewenangan tersebut, beberapa daerah di Indonesia mulai melakukan inisiatif-inisiatif untuk mengembangkan potensi daerahnya masing-masing. Hal ini dapat dilihat dari mulai maraknya pemilihan kepala daerah hingga hingar-bingar upaya pembentukan identitas daerah masing-masing.20 Peraturan daerah atau yang biasa disebut dengan perda, sebagai produk hukum pemerintah daerah, dapat dimaknai sebagai rambu-rambu hukum dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di daerah. Perda sebagai rambu-rambu hukum, secara substansif berisi nilai-nilai yang diyakini dapat memberikan arah bagi para pemimpin daerah dalam menjalankan kekuasaannya sehingga mampu membawa rakyat daerah pada kondisi yang sejahtera lahir dan batin. Perda selain menjadi rambu-rambu, juga dapat difungsikan sebagai instrumen pemerintahan, pemelihara serta untuk mempromosikan nilai dan prinsip-prinsip tertentu. Bertolak dari fakta bahwa perda merupakan nilai-nilai asli masyarakat daerah yang dipositifkan,21 dalam perjalanannya telah memunculkan perda yang beraneka warna, salah satunya adalah perda bernuansa agama, perda bermotif agama atau perda bias agama yang kemudian secara generik diistilahkan dengan perda syariah.
Regulasi tentang pemerintahan daerah membentuk kecenderungan produksi perda di seluruh wilayah Indonesia meningkat. Produktivitas perda itu dapat dilihat sebagai sesuatu yang positif, yakni sebagai respon untuk menata ulang hubungan kekuasaan yang sentralistis menuju desentralistis. Otonomi daerah yang diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia mempunyai makna penting dan memberikan kontribusi positif bagi setiap daerah yang hendak mengembangkan potensi yang dimilikinya. Penataan kembali hubungan kekuasaan ini membuka peluang perubahan pada pemaknaan tentang peran para pemangku kepentingan dalam tata pemerintahan daerah. Pada penetapan kembali inilah interaksi budaya (dalam bentuk agama, adat dan lain sebagainya) dan politik saling
19 Muntoha, “Otonomi Daerah”, 261. 20 Dampak undang-undang tersebut cukup berarti di tingkat kota dan kabupaten,
pemerintah daerah menyikapinya dengan membenahi berbagai sektor, membangun berbagai dasar hukum sebagai pengatur aktivitas di daerah. Nelti Anggraini, Membaca Partisipasi Publik dalam Mendorong Lahirnya Produk Undang-undang Berdimensi
Agama di Sumatra Barat, dalam http://neltianggraini.blogspot.com/, akses tanggal 23 April 2011, 08:14 WIB.
21 Suroso, Perda Syariah dalam Sistem Hukum Nasional, sebagaimana dimuat dalam http://fh.wisnuwardhana.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id= 42&Itemid=1 akses tanggal 5 Oktober 2011, 10:33 WIB.
6 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
mempengaruhi untuk menentukan peran yang baru. Proses penetapan ini dapat menghasilkan hubungan kuasa yang menguntungkan atau merugikan, tergantung pada siapa yang terlibat dalam proses ini dan kepentingan apa yang bermain di dalamnya.
Salah satu potensi kearifan lokal yang menjadi ciri khas Indonesia adalah eksistensi adat yang hidup di tengah-tengah masyarakatnya. Hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dalam sejarah panjang di Indonesia dan telah banyak diteliti oleh pakar hukum ataupun ahli sejarah. Pada awalnya, ahli hukum barat mempertentangkan kedua objek ini dengan melakukan analisis berdasarkan pendekatan konflik karena kebutuhan politik penjajahan. Sejarah sosial tentang konfrontasi antara adat dan Islam di Minangkabau22 pada era kolonial merupakan indikasi yang jelas tentang pola hubungan hukum adat dan Islam. Pada era yang sama juga terbukti bahwa hukum adat dan hukum Islam di Indonesia dapat hidup berdampingan dan saling melengkapi.
Masyarakat hukum adat Minangkabau yang merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat beranggapan bahwa kebijakan otonomi daerah adalah sebuah peluang untuk mengembalikan peran masyarakat adat yang secara perlahan terdegradasi pada masa pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru.23 Salah satu kebijakan daerah yang paling awal merespon kebijakan otonomi daerah di Sumatera Barat adalah penerapan bentuk sistem pemerintahan nagari24
melalui Perda Nomor 9 Tahun 2000
22 Minangkabau merupakan salah satu contoh yang paling sering diambil dalam
menjelaskan hubungan antara hukum adat dan Islam para era kolonial. Untuk mengetahui lebih jauh, simak penjelasan rincinya dalam Ratno Lukito, Islamic Law And
Adat Encounter: The Experience Of Indonesia (Jakarta: INIS, 1998), 27-56. 23 Ismail Zubir, Religiusitas Masyarakat Minangkabau dan Kebebasan
Beragama/HAM Pasca Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999. Sebagaimana yang dimuat dalam http://agama.kompasiana.com/2011/01/21/religiusitas-masyarakat-minangkabau-dan-kebebasan-beragamaham-pasca-uu-otonomi-daerah-no-22-tahun-1999/. Akses tanggal 18 Oktober 2011, pukul 12:09 WIB. Pemberlakukan Undang-undang Nomor 5 tahun 1975 tentang Pemerintahan Desa telah secara tidak langsung telah menghilangkan konsep nagari sebagaimana yang sudah dipakai sejak lama oleh masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Sebenarnya usaha untuk mengembalikan sistem pemerintahan nagari telah lama dilaksanakan di Sumatera Barat, hal ini terlihat dengan adanya Perda Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari sebagai Sebuah Kesatuan Hukum Adat.
24 Nagari dalam konsep tradisional Minangkabau dipahami sebagai sebuah kesatuan adat, ulayat di Sumatera Barat, atau semacam republik mini yang pernah dikenal dalam sejarah Yunani Kuno. Akan tetapi nagari dalam pengertian administratif kemudian dipahami sebagai pemerintahan terendah seperti halnya desa di Jawa, nanggroe di Aceh, marga di Tapanuli, kampong di Palembang dan sebagainya. Sesuai dengan Perda Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan
PENDAHULUAN | 7
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
dan Perda Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari. Merujuk pada konsideran Perda ini, alasan pendorong utama pembentukan regulasi ini adalah adanya peluang pemenuhan kebutuhan sendiri berdasarkan konsep otonomi dan desentralisasi. Hal ini juga disokong oleh semangat adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah;
syarak mangato, adat mamakai; alam takambang jadi guru (adat bersendikan agama, agama bersendikan Alquran; agama menggariskan, adat melaksanakan; alam terbuka menjadi pembelajaran). Keberadaan Perda ini merintis kemunculan semangat babaliak ka nagari, babaliak ka
surau (kembali ke nagari, kembali ke surau) dalam pembangunan masyarakat hukum adat Minangkabau di Sumatera Barat era kontemporer. Usaha ini kemudian dipopulerkan dengan istilah mambangkik batang tarandam.
Semangat babaliak ka nagari babaliak ka surau25 yang dikibarkan
pasca ditetapkannya Perda Nomor 9 Tahun 2000 begitu mengakar kuat dalam masyarakat. Hal ini sangat didukung karena semangat masyarakat untuk mengembalikan jati diri Minangkabau seutuhnya. Dari tinjauan sosiologis, nagari merupakan konsep kosmologis yang di dalamnya terkandung kehidupan religius yang bersifat kontemplatif transenden. Secara holistik, dalam nagari tidak hanya diurus masalah administrasi pemerintahan, namun lebih pada hal-hal yang bersifat transenden, seperti kehidupan surau.26 Kembali pada konsep surau era otonomi daerah yang dimaksud bukanlah menerapkan konsep surau tradisional seperti masa lampau. Namun lebih pada penekanan terhadap fungsi surau sebagai
Nagari, pasal 1G disebutkan bahwa nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah, yang mempunyai wilayah tertentu, disertai dengan batas-batas wilayah, mempunyai harta kekayaaan dan berhak mengatur rumah tangganya dan memilih pimpinan pemerintahan sendiri.
25 Konsep babaliak ka nagari, babaliak ka surau dimaknai sebagai upaya revitalisasi nilai-nilai tradisional Minangkabau. Konsep ini juga menunjukkan keterkaitan yang erat antara nilai-nilai adat dengan Islam dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.
26 Surau merupakan bangunan peninggalan kebudayaan masyarakat sebelum datangnya Islam. Surau dalam sistem adat Minangkabau adalah kaum, suku atau indo. Sidi Gazalba, Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam (Jakarta: Pustaka Antara, 1983), 314-316. Kehidupan surau pada masyarakat tradisional di Minangkabau dilatarbelakangi oleh kondisi sosiokultural pada waktu itu. Dalam rumah adat Minangkabau tidak disediakan sebuah kamar khusus bagi laki-laki. Remaja laki-laki di Minangkabau menginap di surau. Azyumardi Azra, Surau: Pendidikan Islam
Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003), 8. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Azra dalam buku tentang biografinya. Andina Dwifatma, Cerita Azra: Biografi Cendikiawan Muslim Azyumardi Azra (Jakarta: Erlangga, 2011), 7-8.
8 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
media kontrol dalam menyaring pengaruh budaya karena semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini. Babaliak ka nagari babaliak ka surau merupakan suatu program Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat pada masa bergulirnya otonomi daerah.
Selain untuk keperluan desentralisasi kekuasaan atau kewenangan dalam pengertian geografis, dengan kembali pada sistem pemerintahan bernagari, juga diharapkan the land of Minangkabau menjadi lebih berdaya. Hal ini terkait dengan upaya revitalisasi kembali peran ninik mamak, alim ulama dan cadiak pandai selaku kontrol sosial di tengah masyarakat. Perdebatan yang kemudian muncul adalah, nagari model apa dan kapan yang kemudian akan dirujuk, karena sistem pemerintahan nagari telah mengalami serangkaian proses dinamisasi. Dinamisasi bentuk pemerintahan nagari dipengaruhi oleh masuknya Islam dan kedatangan kolonial. Nagari juga mengalami dinamisasi pada era Orde Lama dan Orde Baru. Persoalan lainnya yang kemudian muncul adalah bahwa pada satu sisi ada tuntutan menggebu bagaimana Sumatera Barat dalam pengertian Minangkabau tetap menjadi otentik, karena di Sumatera Barat umumnya adalah daerah di mana secara turun-temurun telah terjadi kedekatan yang kuat antara adat dengan agama. Dalam banyak hal, masalah-masalah tersebut sulit dipisahkan walaupun mudah dibedakan. Kedekatan ini cukup mengikat dan menyatu.27 Agama menjadi tergantung pada adat atau tradisi setempat, sebaliknya adat atau tradisi mendapatkan muatan agama, sehingga dalam beberapa kasus di beberapa daerah tertentu, di antara keduanya terlihat menyatu. Sikap adat atau tradisi menjadi sama dengan sikap agama, atau sikap agama terhadap persoalan setempat menjadi sama dengan sikap adat atau tradisi setempat.
Bagi masyarakat Minangkabau,28 falsafah adat basandi syarak,
syarak basandi Kitabullah secara tidak langsung menyatakan bahwa
27 Adanya saling keterkaitan dan menyatunya antara adat dan ajaran Islam di
Minangkabau tergambar jelas dalam petatah; Sutan Muncak mati tarambau, ka ladang
mambao ladiang, adat jo syarak di Minangkabau bak aua jo tabiang, sanda manyanda
kaduonyo (Sutan Muncak meninggal terjatuh, pergi ke ladang membawa parang, adat dan syarak di Minangkabau seumpama aur dan tebing, saling bersandar di antara keduanya). Julius Dt. Malako nan Putiah, Mambangkik Batang Tarandam Dalam Upaya
Mewariskan dan Melestarikan Adat Minangkabau Menghadapi Proses Modernisasi
Kehidupan Bangsa (Jakarta: Arena Seni, 2007), 3. 28 Sistem adat Minangkabau mempunyai keunikan dalam hubungan antara
adatnya dengan nilai-nilai keislaman. Menurut filsafat hidup masyarakat Minangkabau, tidak ada pertentangan antara adat dengan nilai-nilai Islam. Keduanya berjalan beriringan tanpa harus terlibat konflik, karena adat sebagai institusi kebudayaan dalam masyarakat mendapat posisi yang selaras dengan harmonisasi nilai-nilai Islam. Azyumardi Azra, Surau, 2.
PENDAHULUAN | 9
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
masyarakat Minangkabau hanya mengenal satu ideologi, yaitu Islam dan adat yang dipakai dalam interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat. Religiusitas masyarakat Minangkabau tercermin dari totalitas keberagamaan masyarakatnya terhadap keyakinan, pengamalan, penghayatan, pengetahuan, dan konsekuensi keberagamaan.29 Prinsip tersebut diimplementasikan dalam regulasi bernuansa syariah yang banyak diterapkan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat.
Adanya integrasi nilai-nilai adat dan Islam di Minangkabau tidak lepas dari rentetan panjang sejarah masuknya Islam ke ranah Minangkabau. Islam masuk ke Minangkabau pada abad ke-VII.30 Nenek moyang orang Minangkabau pada saat itu sudah terbiasa membaca ayat-ayat Tuhan31 yang terdapat di alam ini, dengan sendirinya tidak menolak ajaran Islam.32 Falsafah adat Minangkabau itu semakin mengalami
29 Ismail Zubir, Religiusitas Masyarakat Minangkabau dan Kebebasan
Beragama /HAM Pasca UU Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 dalam http://agama.kompasiana.com/ 2011/01/21/religiusitas-masyarakat-minangkabau-dan-kebebasan-beragamaham-pasca-uu-otonomi-daerah-no-22-tahun-1999/ akses tanggal 5 Oktober 2011, 11:23 WIB.
30 Ada dua pendapat yang berbeda terkait masuknya Islam ke Minangkabau. Pendapat pertama menyatakan bahwa Islam masuk ke Minangkabau pada abad ke-VII. Hal ini berdasarkan ketetapan hasil Seminar Masuknya Islam ke Indonesia yang dilaksanakan di Medan pada 17-20 Maret 1963 dan di Langsa pada 25-30 September 1980. Keterangan lebih lanjut bisa disimak dalam Sanusi Latief, Gerakan Kaum Tua di Minangkabau (Desertasi SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1987), 43-44. Pendapat kedua menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-XIII. Pendapat ini dipelopori oleh sarjana-sarjana barat, seperti Snouck Hurgronje. Pendapat Snouck Hurgronje didasarkan pada alasan bahwa patokan masuknya Islam ke Indonesia adalah peristiwa keruntuhan Baghdad karena adanya serangan Hulagu Khan pada tahun 1258. Pendapat ini diperkuat dengan adanya catatan perjalana Marco Polo tahun 1292 dan catatan Ibnu Batutah pada tahun 1345 tentang Kerajaan Islam Perlak dan Samudera Pasai di Aceh. Keterangan lenih lanjut dapat ditemukan dalam Snouck Hurgronje, Islam
di Hindia Belanda (Jakarta: Bhratara, 1973), 13-14. 31 Sebelum masuknya ajaran Islam ke nusantara ini, atau bahkan sebelum
masuknya ajarah Hindu pada abad ke-I, nenek moyang orang Minangkabau telah menyusun aturan dan norma kehidupan bermasyarakat dalam bentuk adat Minangkabau yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan alam nyata. Hal ini tergambar dalam falsafah adat Minangkabau yang menyatakan bahwa alam takambang jadi guru (alam terbuka menjadi guru) dengan menggunakan 4 titik tolak yang dijadikan landasan dasar, yaitu; raso (rasa), pareso (karsa), alua (alur) dan patuik (kepatutan). Julius Dt. Malako nan Putiah, Mambangkik Batang Tarandam, 1. Lihat juga dalam Idrus Hakimy Dt. Rajo Panghulu, Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), 16. Lihat juga dalam Ramayulis, dkk. Pemahaman Ninik Mamak
Pemangku Adat Minangkabau Terhadap Nilai-nilai ABS-SBK (Padang: IAIN Imam Bonjol Press, 2009), 17.
32 Julius Dt. Malako nan Putiah, Mambangkik Batang Tarandam, 2.
10 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
adaptasi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan zamannya dan mengalami penyempurnaan pada masa gerakan Kaum Paderi.
Jauh sebelum Islam datang ke nusantara, masyarakat Minangkabau telah mempunyai tata nilai, aturan hidup (way of life) yang jelas. Adat yang dipahami sebagai doktrin sosial masyarakat telah berlaku secara universal dalam tatanan masyarakat Minangkabau tradisional. Hal ini dijelaskan dalam petatah masyarakat Minangkabau, jikok dibalun
sabalun kuku; jikok dikambang saleba alam; walau sagadang bijo labu;
bumi jo langik ado di dalam (apabila digumpal sebesar kuku; apabila digelar seluas alam; meskipun hanya sebesar biji labu; namun ada bumi dan langit di dalamnya). Islam datang ke Minangkabau membawa perubahan budaya.33 Akulturasi Islam dan budaya bukannya terjadi tanpa perjuangan. Hal ini dibuktikan dengan adanya gerakan Islam puritan Kaum Paderi hingga terjadinya Perang Paderi yang dianggap sebagai titik klimaks persinggungan dan akluturasi antara ajaran Islam dan budaya Minangkabau.
Secara kultural, masyarakat Minangkabau selalu menjadikan adat alam Minangkabau sebagai dasar bangunan kehidupan mereka. Adat biasanya dipahami sebagai suatu kebiasaan setempat yang mengatur interaksi masyarakat dalam suatu komunitas. Oleh masyarakat Minangkabau, adat mempunyai makna ganda. Adat berarti kumpulan kebiasaan setempat, dan adat juga dianggap sebagai keseluruhan sistem struktural masyarakat. Dalam konteks ini, adat adalah seluruh sistem nilai, dasar dari keseluruhan penilaian etis dan hukum. Tidak hanya sampai di situ, adat juga dipandang sebagai sumber dan harapan sosial yang mewujudkan pola prilaku ideal.34 Atas keyakinan terhadap adat sebagai sistem nilai, sistem norma, sistem sikap dan sistem prilaku, maka masyarakat Minangkabau dituntun untuk memahami hakikat kehidupan, hakikat hubungan antar sesama manusia, hakikat hubungan antar individu dengan komunitas dalam masyarakat dan lain sebagainya.
Filosofi adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah merupakan puncak dari persentuhan, perbenturan, penyesuaian dan perpaduan antara adat Minangkabau yang sudah ada semenjak dari nenek
33 Ismail Zubir, Religiusitas Masyarakat Minangkabau dan Kebebasan
Beragama/HAM Pasca Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 22 tahun 1999. Sebagaimana yang dimuat dalam http://agama.kompasiana.com/2011/01/21/religiusitas-masyarakat-minangkabau-dan-kebebasan-beragamaham-pasca-uu-otonomi-daerah-no-22-tahun-1999/, akses tanggal 5 Oktober 2011, 11:23 WIB.
34 De Josselin de Jong, “Minangkabau”, dalam Islam and Society in Southeast
Asia, eds. Taufiq Abdullah & Sharon Siddique (Singapura: Institute of Southeast Studies, 1987), 85.
PENDAHULUAN | 11
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
moyang dengan ajaran Islam yang datang kemudian.35 Lahirnya falsafah ini tidaklah muncul begitu saja, akan tetapi melalui masa yang panjang. Bahkan dalam masa yang panjang itu terjadi perbenturan/konflik antara adat dan agama Islam. Hal ini terjadi karena adat Minangkabau sudah mempunyai tatanan kehidupan baik secara individu maupun secara bermasyarakat. Di samping itu Islam yang datang kemudian juga membawa tatanan dalam kehidupan dalam segala segi dan juga menuntut ketaatan dari pada pemeluknya. Dengan kedatangan Islam itu bertemulah dua tatanan kehidupan di alam Minangkabau yang masing-masing menuntut kepatuhan dari umat, masyarakat penganut atau pendukungnya.
Keberadaan perda-perda berdimensi syariah di Sumatera Barat36 selalu dikaitkan dengan faktor sosial budaya masyarakat Minangkabau yang identik dengan ajaran Islam sebagaimana tercermin dalam filosofi adat Minangkabau yakni adat basandi syarak-syarak basandi Kitabullah. Ajaran Islam begitu kental dengan kebudayaan yang dianut oleh masyarakat Minangkabau. Demikian juga halnya dengan konsistensi masyarakat Minangkabau dalam menjalankan serta mematuhi peraturan adatnya. Pada satu sisi, keberhasilan upaya pihak pemerintah daerah dalam mengintegrasikan serta mentransformasikan nilai-nilai ajaran Islam dan budaya Minangkabau dalam regulasinya akan memicu beberapa pergeseran dan konflik sosial dalam masyarakat yang pada akhirnya akan berujung pada perubahan sosial pada masyarakat Minangkabau.
Berdasarkan pemaparan di atas, muncul suatu ketertarikan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai usaha mambangkik
batang taradam di Sumatera Barat dengan menyelidiki pengaruh integrasi adat dan Islam terhadap kecenderungan pembangunan hukum di Sumatera Barat era otonomi daerah dan desentalisasi kekuasaan. Oleh
35 Ramayulis, “Traktat Marapalam Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi
Kitabullah: Diktum Keramat Konsensus Pemuka Adat dan Pemuka Agama Dalam Memadukan Adat dan Islam di Minangkabau Sumatera Barat” (2010), makalah ini dipresentasi pada Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) ke-10 dengan tema Menampilkan Kembali Islam Nusantara, di Banjarmasin Kalimantan Selatan pada 1-4 November 2010, 7.
36 Menarik dicermati untuk konteks regional Sumatera Barat, yakni aspirasi tentang penegakan syariat Islam dijalur politik dalam bentuk Perda ini ditangkap dalam perspektif yang berbeda dari yang dimaksud masyarakat. Jika dalam perspektif masyarakat, penerapan syariat Islam berarti dijalankannya ajaran-ajaran moral agama dengan sungguh-sungguh dengan pendekatan kultural-subtansial, maka dalam perspektif elit, penerapan syariat Islam lebih menjadi sarana politik dan kepentingan birokrat. Sulis Syakhsiyah Annisa, Perda Wajib Berbusana Muslim di Sijunjung dalam http://syakhsiyah.wordpress.com/2009/09/18/64/, akses tanggal 21 April 2011, 15:13 WIB.
12 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
sebab itu, penelitian ini dilaksanakan di bawah judul “Rekonstruksi Adat Minangkabau dalam Pemerintahan Nagari Era Otonomi Daerah: Kajian Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 jo. Perda Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari”.
B. Masalah 1. Identifikasi Masalah
Berdasarkan paparan di atas, dapat diidentifikasikan beberapa masalah yang berkaitan dengan otonomi daerah dan desentralisasi dalam kaitannya dengan hubungan adat dan Islam pada masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, sebagai berikut. a. Proses legislasi peraturan-peraturan daerah yang di dalamnya sarat
dengan muatan syariat Islam; b. Korelasi antara kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi
kekuasaan dengan visi masyarakat Sumatera Barat yang mengusung tema babaliak ka nagari, babaliak ka surau (kembali pada konsep nagari, kembali pada konsep surau);
c. Pengaruh semangat adat basandi syarak, syarak basandi
Kitabullah dalam pola hidup masyarakat Minangkabau dan kecenderungan pemberlakuan hukum positif di Sumatera Barat;
d. Ekuivalensi dan konfrontasi antara peraturan daerah yang bermuatan syariat Islam di Sumatera Barat dengan asas-asas dan norma-norma hak asasi manusia;
e. Hubungan konsep materi hukum Peraturan Daerah dengan Peraturan lainnya yang berada di atasnya dalam hierarki perundang-undangan;
f. Pengaruh integrasi antara nilai-nilai agama Islam dan adat terhadap kecenderungan pembangunan hukum era desentralisasi kekuasaan di Sumatera Barat dan hubungannya dengan teori receptie in complexu, receptie, dan receptie a contrario/receptie
exit.
2. Rumusan Masalah a. Mayor question research dalam penelitian ini adalah
bagaimanakah rekonstruksi hubungan adat dan nilai-nilai Islam masyarakat hukum adat Minangkabau dalam era otonomi daerah di Sumatera Barat?
b. Minor question research guna menunjang pembenukan preposisi, rumusan penelitian ini diturunkan dalam dua bentuk pertanyaan, sebagai berikut.
PENDAHULUAN | 13
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
1) Bagaimanakah pembangunan sistem pemerintahan nagari pada era otonomi daerah di Sumatera Barat?
2) Bagaimanakah pencapaian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat Minangkabau?
3. Batasan Masalah
Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah pengkajian tentang kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat pada era otonomi daerah yang berkaitan dengan sistem pemerintahan nagari dalam Perda Nomor 9 Tahun 2000 jo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari dan pencapaian daerah Sumatera Barat pada era pemerintahan nagari. Fokus kajian ini adalah regulasi mengenai eksistensi adat di Sumatera Barat. Faktor ini representatif untuk dijadikan patokan utama dalam membatasi pembahasan dalam tesis ini.
C. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki upaya rekonstruksi nilali-nilai adat dalam masyarakat hukum adat Minangkabau pada era otonomi daerah dan desentralisasi kekuasaan. Untuk membuktikan hal tersebut, penulis mengadakan penelitian terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada era otonomi daerah terkait dengan sistem pemerintahan nagari serta pencapaian beberapa aspek kehidupan. D. Signifikasi Penelitian
Adapun yang menjadi signifikansi penelitian ini ditujukan kepada beberapa pihak terkait sebagai berikut : 1. Menambah khazanah ilmiah dan menjadi sumber rujukan atau bahan
kajian/pemikiran lebih lanjut dalam proses reformasi dan pembangunan hukum Islam pada skala nasional bagi berbagai pihak yang hendak memahami otonomi daerah dan desentralisasi kekuasaan di Sumatera Barat;
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi terhadap pelaksanaan Perda Nagari di Sumatera Barat sehingga bisa dijadikan kerangka acuan dalam proses pembangunan hukum selanjutnya.
14 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
E. Literature Review
Kajian mengenai Peraturan Daerah di Indonesia pasca-otonomi daerah telah banyak dilakukan oleh akademisi, baik dalam bentuk penelitian individu ataupun kelompok berupa karya ilmiah, buku-buku dan artikel. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap kecenderungan prilaku adat dan keagamaan masyarakat daerah setempat. Meskipun demikian, ditemukan beberapa literatur yang dapat dijadikan perbandingan bagi penelitian ini. Literatur-literatur yang dimaksud tersebut dapat diuraikan, sebagai berikut.
1. Recreating The Nagari: Decentralization in West Sumatera
37 oleh Franz dan Keebet von Benda-Beckmann. Tulisan ini merupakan working paper di Max Planck Institute. Ide-ide dalam tulisan ini kemudian dikembangkan kembali dalam Identitas-identitas Ambivalen: Desentralisasi dan Komunitas-komunitas Politik Minangkabau.38 Temuan utama dalam tulisan ini menyatakan bahwa hubungan antara adat, Islam dan negara telah mengalami pergeseran, namun orang Minangkabau masih memperoleh identitas mereka dari ketiga tatanan normatif tersebut secara bersama. Desentralisasi dan kembali ke nagari bukan hanya terkait dengan rekonfigurasi georafis dan administrastif belaka. Upaya tersebut memungkinkan adanya diferensiasi cukup besar antara kabupaten-kabupaten dan nagari-nagari. Pemerintah telah memperkenalkan pandangan-pandangan dunia sosial dan politis baru tentang modernitas dan pembangunan. Meskipun banyak orang Minangkabau tidak memenui kesulitan dalam mengadopsi ide-ide baru ini, matrilinealitas dan modernitas seringkali dipandang saling mengenyampingkan. Akan tetapi, Minangkabau secara persisten menempati posisi terkemuka dalam ruang politik Negara.
2. Re-Empowering The Art of Elders oleh Gregory L. Acciaioli. Tulisan ini merupakan kajian terhadap upaya revitalisasi adat dalam
37 Franz dan Keebet von Benda-Beckmann, “Recreating The Nagari:
Decentralization in West Sumatera”, Working Paper at Max Planck Institute of Social Antrhopology (Halle/Yalle: 2001), 36-39.
38 Franz dan Keebet von Benda-Beckmann, “Identitas-identitas Ambivalen: Desentralisasi dan Komunitas-komunitas Politik Minangkabau”, dalam Politik Lokal di
Indonesia, eds. Henk Schulte Nordholt, et. all. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), 543-575.
PENDAHULUAN | 15
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
komunitas masyarakat adat To Lindu di Sulawesi Tengah dalam upaya penyelesaian konflik horizontal pada era Indonesia kontemporer. Kesimpulan tulisan ini menyatakan bahwa lembaga-lembaga tradisional non-negara, bahkan dalam bentuknya yang baru dan termodifikasi dapat membantu mempertahankan tertib sosial dan integrasi sosial. Kebangkitan mekanisme adat belakangan ini dalam upaya menyelesaikan sengketa, menghukum kejahatan dan membela korban telah menunjukkan sejumlah keberhasilan dalam konteks komunitas yang relatif tertutup.39
3. Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia oleh Ratno Lukito. Buku ini memfokuskan pembahasan pada tema hukum adat dan hukum Islam sejak zaman kolonialisme hingga masa Orde Baru. Pada periode kolonial Belanda, antara hukum Islam dan hukum adat memasuki masa persinggungan. Ratno Lukito mengambil latar belakang penggambarannya dari peristiwa Perang Paderi yang terjadi di Sumatera Barat. Pada era kependudukan Jepang, persinggungan ini dititikberatkan pada masa mulai terbentuknya peradilan agama bagi masyarakat pribumi. Pada era awal kemerdekaan, pergumulan ini terlihat dalam pembentukan Piagam Jakarta. Namun, pada era Orde Baru, arah perkembangannya lebih terfokus pada pembangunan hukum nasional dengan menyisipkan nilai-nilai agama di dalamnya. Hipotesis penelitian ini menyatakan bahwa pergumulan antara hukum Islam dan adat di Indonesia harus dipandang sebagai hubungan dialogis dibanding konfrontasi. Sebagai suatu pendekatan, aplikasi dari teori konflik terhadap hubungan antara hukum adat dan Islam adalah arbiter sifatnya, karena hanya melalui pemahaman terhadap landasan-landasan doktrinal saja.40
39 Gregory L. Acciaioli, “Re-Empowering The Art of Elders: The Revitalization
of Adat Among The To Lindu People of Central Sulawesi and Throughout Contemporary Indonesia”, dalam Beyond Jakarta: Regional Autonomy and Local
Societies in Indonesia, ed. M. Sakai (Adelaide: Crawford House, 2002), 221-216. 40 Ratno Lukito, Islamic Law, 94. Lihat juga dalam Ratno Lukito, “Law and
Politics in Post-Independence Indonesia: a Case Study of Religious and Adat Courts”, Shari’a and Politics in Modern Indonesia, eds. Askal Salim and Azyumardi Azra (Singapore: ISEAS Publishing, 2003), 17-29. Tulisan ini juga telah diterbitkan sebelumnya sebagai “Hukum dan Politik Pasca-Kemerdekaan Indonesia: Studi Kasus Agama dan Hukum Adat”, Studia Islamika: Jurnal Kajian Islam Indonesia 6, Nomor 3 (1999): 65-86. Tulisan ini juga dimasukkan dalam buku Ratno Lukito selanjutnya, lihat Ratno Lukito, Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi
dalam Sistem Hukum Indonesia (Jakarta: Alvabet, 2008).
16 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
4. Surau: Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi oleh Azyumardi Azra. Ada beberapa poin penting yang disoroti dalam buku ini, mulai dari sejarah surau di Minangkabau hingga semakin terpinggirkannya surau karena semakin menjamurnya sistem pendidikan modern dalam konsep pesantren. Penulisnya juga menyinggung keberadaan surau di Minangkabau pada masa desentralisasi. Hal ini terlihat dalam bagian akhir yang menyatakan bahwa dalam era otonomisasi dan desentralisasi di Sumatera Barat, surau kembali menjadi public discourse di kalangan masyarakat Minangkabau sendiri. Akan tetapi, pada saat yang sama, surau telah hilang dari nomenklatur kontemporer kelembagaan pendidikan Islam baik di tengah Sumatera Barat ataupun nasional. Dengan kenyataan ini, dapat disimpulkan bahwa belum ada indikator yang meyakinkan bagi kebangkitan kembali surau sebagai lembaga full-fledged pendidikan, agama, sosial, budaya dan adat. Surau dalam sistem sosial-budaya masyarakat Minangkabau lebih dari sekedar institusi pendidikan keagaaman dan sekaligus merupakan institusi adat dan budaya.41
5. Nagari, Demokrasi Lokal dan Good Governance: dalam Riwayat Muhammad Hatta oleh Indra J. Piliang. Dalam makalahnya ini, Indra J. Piliang menyatakan bahwa pada saat ini sudah diputuskan dua Peraturan Daerah tentang kembali ke nagari dan kembali ke surau di Sumatera Barat. Kedua Perda ini juga diikuti dengan perda-perda lain yang secara keseluruhan menginginkan berkembangnya Sumatera Barat sebagai entitas yang punya keunikan adat-istiadat. Perlu diadakan evaluasi dan penelitian lanjutan untuk melihat apakah perda-perda itu terimplementasikan dengan baik, atau hanya semata-mata mengangkat persoalan simbolis ke ranah struktural. Nagari, dalam sejumlah hal, bisa membentuk kedinamisan tinggi dalam melahirkan demokrasi lokal, sekaligus penegakkan prinsip-prinsip good
governance.42
41 Azyumardi Azra, Surau, 139-150. 42 Indra J. Piliang, “Nagari, Demokrasi Lokal dan Good Governance: dalam
Riwayat Muhammad Hatta”. Makalah ini disampaikan dalam acara Temu Nasional Cendikiawan Minang Indonesia dengan tema Sumatera Barat Masa Depan: Sebuah Gagasan Menatap Tatanan baru dalam Bingkai Indonesia. Acara ini diadakan oleh Forum Komunikasi Mahasiswa Minang Universitas Gajah Mada di Yogyakarta pada tanggal 10-11 Februari 2004.
PENDAHULUAN | 17
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
6. Konversi Agama dalam Adat Minangkabau oleh Firdaus, Tesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2006. Penelitian tesis ini adalah justifikasi adat di Minangkabau terhadap prilaku konversi agama dalam kaitannya dengan aporisme adat yang islamis. Interpretasi terhadap hal ini melahirkan paradigma komunalisme keagamaan di mana identitas kebudayaan dikaitkan dengan agama yang dianut. Temuan dalam tesis ini menyimpulkan bahwa Islam dan adat di Minangkabau mempunyai relasi yang sangat kuat. Hal ini tergambar dalam falsafah adat yang menggambarkan agama sebagai landasan adat. Lebih jauh lagi, agama Islam merupakan faktor penentu terhadap seseorang yang berasal dari Minangkabau.43
7. Otonomi Sepenuh Hati oleh Jazuli Juwaini. Buku ini menjelaskan
kerangka normatif implementasi otonomi daerah dan desentralisasi serta beberapa ulasan tentang evaluasi pelaksanaan otonomi daerah pasca adanya ketentuan perundang-undangan yang telah diundangkan dan dilaksanakan. Menariknya, analisis yang dilakukan oleh juga menitikberatkan pembahasan pada hubungan desentralisasi kekuasaan dengan konsep good governance. Pada bagian akhir tulisannya, dinyatakan bahwa kepemimpinan memegang peran penting dalam konsep desentralisasi. Oleh sebab itu, tuntutan good governance, clean government dan reformasi birokrasi harus dilaksanakan dan dijadikan acuan utama oleh kepala daerah dan anggota lembaga perwakilan daerah. Pencapaian otonomi pada saat ini harus dijadikan sebagai sebuah titik balik (point of return). Otonomi yang kita raih harus terus berjalan dan lebih ditingkatkan lebih ekstensif. Bukan untuk mengingkari negara kesatuan, namun untuk lebih memberi ruang kepada potensi dan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Inilah makna sesungguhnya dari otonomi sepenuh hati.44
8. Simbur Cahaya: Studi tentang Pergumulan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Kesultanan Palembang Darussalam oleh Muhammad Adil, Desertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009. Penelitian ini mempunyai fokus pada penyelidikan mengenai pola akomodasi hubungan hukum Islam dan hukum adat dengan menggunakan Kitab Simbur Cahaya sebagai bahan kajian utama.
43 Firdaus, “Konversi Agama dalam Adat Minangkabau” (Tesis SPs UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta, 2006). 44 Jazuli Juwaini, Otonomi Sepenuh Hati, 103.
18 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Penelitian ini menyimpulkan bahwa pergumulan hukum Islam dan hukum adat di Nusantara mempunyai corak akomodatif. Akomodasi hukum Islam terhadap hukum adat terlihat dalam aspek hukum keluarga pada Undang-undang Simbur Cahaya yang menjadi rujukan hukum pada Kerajaan Palembang Darussalam. Lebih jauh lagi, penelitian ini menyatakan bahwa hukum Islam dan hukum adat telah hidup secara berdampingan dengan damai, baik secara teoritis dan praktisnya. Hukum Islam dapat mengakomodasi efektivitas hukum adat, sementara itu hukum adat menerima hukum Islam sebagai titik kesempurnaan.45
9. Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi oleh
Mohammad Mahfud M.D. Pembahasan mengenai otonomi daerah dalam buku ini dikaji dalam satu bab tersendiri. Penejelasan dalam buku ini memberikan peninjauan keberadaan otonomi daerah dan desentralisasi kekuasaan dari sisi politik hukumnya. Mohammad mahfud M.D. menyimpulkan bahwa paradigma yang harus dianut oleh undang-undang pemerintahan daerah haruslah diubah dari paradigma pembangunan ke arah paradigma pelayanan dan pemberdayaan dengan pola kemitraan yang desentralistik. Paradigma yang baru tersebut tidak dapat dikatakan sebagai anti pembangunan, sebab pembangunan tetap digalakkan dalam kerangka pemberdayaan daerah dan pelayanan pemerintah dengan pola kemitraan yang demokratis.46
10. Otonomi Daerah dan Desentralisasi yang ditulis oleh Utang
Rosidin. Dalam buku ini, dikupas tuntas segala aspek yang berkaitan dengan otonomi daerah dan desentralisasi. Hal ini dijelaskan secara rinci berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan otonomi daerah. Dalam salah satu pembahasannya, dinyatakan bahwa fenomena maraknya perda bernuansa syariat Islam dalam penyelenggaraan otonomi daerah di berbagai daerah berkaitan dengan hal berikut. Pertama, terbukanya peluang lewat otonomi daerah (desentralisasi). Kedua, aspirasi permanen sebagian kelompok Islam untuk memasukkan hukum Islam ke dalam hukum nasional. Karena
45 Muhammad Adil, “Simbur Cahaya: Pergumulan Hukum Islam dan Hukum
Adat dalam Kesultanan Palembang Darussalam” (Desertasi SPs UIN syarif Hidayatullah Jakarta, 2009).
46 Moh. Mahfud M.D., Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 222.
PENDAHULUAN | 19
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
upaya memasukkan tujuh kata pada Piagam Jakarta dalam amandemen UUD tidak berhasil, kecenderungan itu bergeser ke tingkat daerah melalui Peraturan Daerah.47
11. Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah
Secara Langsung oleh Rozali Abdullah. Dalam buku ini diuraikan secara mendetail setiap hal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 serta hubungannya dengan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam buku ini juga dijelaskan secara rinci mengenai mekanisme pengaturan pemerintahan pada tingkat daerah. Pada akhir tulisannya, dinyatakan bahwa efektivitas pelaksanaan undang-undang ini tidak bisa dilepaskan dari kehadiran peraturan pelaksanaannya. Sementara pada saat ini, peraturan pelaksanaan itu belum terwujud dan sudah pasti akan membutuhkan waktu lama untuk mengaturnya mengingat luasnya materi yang diatur dalam regulasi tersebut.48
12. Legislative Drafting oleh Jazim Hamidi dan Kemilau Mutik. Materi dalam buku ini lebih menitikberatkan pada pembahasan naskah akademik dalam upaya pembentukan peraturan daerah. Fokus pembahasannya adalah mengenai kedudukan hukum, urgensi serta implikasi hukum naskah akademik terhadap pembentukan peraturan daerah. Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan teori pembentukan undang-undang dengan menggunakan pendekatan statute approach, conceptual approach dan historical approach. Naskah akademik memegang peranan penting dalam pembentukan peraturan daerah. Naskah akademik bisa menjadi tolok ukur dan pertanggungjawaban ilmiah dalam pembentukan peraturan daerah. Implikasi hukum naskah akademik adalah perannya sebagai bandul penyeimbang antara state law dengan living law dalam masyarakat.49
13. Kesewenang-wenangan Penerapan Hukum Syariah oleh Sudarto.
Artikel ini menyatakan bahwa implementasi konsep desentralisasi dengan berbagai penyebutannya masih menyisakan persoalan, karena kuatnya kecenderungan reinventing local yang dalam penampakannya menjelma menjadi primordialisme sempit. Fenomena itu menjadi
47 Utang Rosidin, Otonomi Daerah, 145. 48 Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas, 183-184. 49 Jazim Hamidi dan Kemilau Mutik, Legislative Drafting (Yogyakarta: Total
Media, 2011), 179-182.
20 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
semakin terlihat pada beberapa daerah pada daerah yang mempunyai kedekatan sangat kuat antara tradisi lokal dengan agama. Agama menjadi tergantung pada adat atau tradisi setempat, dan sebaliknya adat atau tradisi setempat mendapatkan muatan agama, sehingga dalam beberapa kasus keduanya menyatu, sikap adat atau tradisi menjadi sama dengan sikap agama, dan sebaliknya sikap keagamaan menjadi sama dengan sikap adat atau tradisi setempat. Hal ini terjadi biasanya pada daerah-daerah di mana budaya setempat menyatu dengan agama yang dominan di daerah tersebut. Hubungan antara budaya lokal dan agama yang tidak jelas garis pembatasnya itu dapat dilihat dalam konteks masyarakat seperti, daerah Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, dan dalam bentuk jargon-jargon adat juga dapat dijumpai di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, dan lain-lain. Sebagian sosiolog dan juga pengamat politik melihat fenomena bangkitnya sentimen agama itu lebih sebagai politisasi agama, atau sebagai bentuk populisme Islam baru.50
14. Religiusitas Masyarakat Minangkabau dan Kebebasan Beragama/HAM Pasca Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 oleh Ismail Zubir. Dalam tulisan yang dipublikasikan pada Kolom Opini Harian Kompas tanggal 11 Januari 2011 ini, dinyatakan bahwa setelah diberlakukan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, pemerintahan terendah di Sumatera Barat kembali pada sistem pemerintahan nagari, dengan tujuan agar masyarakat Minangkabau dapat menata pola interaksi sosialnya secara mandiri. Regulasi-regulasi bernuansa syariah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat merupakan imbas dari religiusitas masyarakat Minangkabau yang dikenal sangat memegang teguh ajaran agama. Menilik pada sejarah pergumulan antara adat dan ajaran Islam di Minangkabau, tergambar adanya suatu proses penyesuaian antara adat dan ajaran Islam. Hal ini bukanlah suatu proses yang saling menyingkirkan, karena kedua aturan itu dianggap sama-sama baik dan berguna oleh masyarakat Minangkabau. Semangat revitalisasi ajaran Islam merupakan cita-cita luhur sebagian besar masyarakat Minangkabau karena falsafah adat Minangkabau telah menyatakan secara tegas adat basandi syarak,
syarak basandi Kitabullah sebagai motto hidup masyarakatnya.
50 Sudarto, Kesewenang-wenangan Penerapan Hukum Syariah. Sebagaimana
yang dimuat dalam http://kiayimassudarto.blogspot.com/2011/04/kesewenang-wenangan-penerapan-hukum. html akses tanggal 18 Oktober 2011, 16:55 WIB.
PENDAHULUAN | 21
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Falsafah adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah memang tidak serta merta mejadikan masyarakat Minangkabau sebagai masyarakat Islamis. Namun, falsafah tersebut memotivasi masyarakat Minangkabau untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Islam yang selama ini telah dianut oleh masyarakat dan mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terlepas apakah falsafah tersebut bertentangan dengan nilai-nilai HAM/kebebasan beragama atau tidak, masyarakat telah menyepakati falsafah tersebut menjadi way of life-nya orang Minangkabau.
F. Metodologi Penelitian 1. Paradigma Penelitian dan Metode Pendekatan
Paradigma yang dipergunakan adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitikberatkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada merincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait.51 Tujuan dipergunakannya pendekatan tersebut adalah dengan harapan dapat menemukan dan memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit dipahami secara komprehensif.
Metode pendekatan52 yang dipergunakan dalam penelitian ini berbentuk grounded theory. Grounded theory merupakan penelitian kualitatif yang berakar pada konstruktivisme, atau paradigma keilmuan yang mencoba mengkonstruksi atau merekonstruksi teori atas suatu fakta yang terjadi53 di lapangan berdasarkan data empirik. Konstruksi atau rekonstruksi teori itu diperoleh melalui analisis induktif atas seperangkat data emik berbentuk korpus yang diperoleh berdasarkan pengamatan lapangan. Pendekatan tersebut dipilih dalam penelitian ini guna memperoleh persepsi baru dari situasi yang
51 Mudjia Rahardjo, Jenis dan Metode Penelitian Kualitatif. Sebagaimana yang
dimuat dalam http://www.mudjiarahardjo.com/component/content/215.html?task=view, akses tanggal 10 Oktober 2011, 14:09 WIB.
52 Menggunakan suatu pendekatan berarti juga secara eksplisit menerima asumsi-asumsi dan prioritas tertentu, termasuk juga komitmen untuk menggunakan metodologi hingga batas-batasnya, untuk menjelaskan fenomena tersebut. Peter Connolly, “Pendahuluan”, dalam Approaches to the Study of Religion, ed. Peter Connolly, terjemahan Imam Khoiri (Yogyakarta: LKiS, 2002), 4.
53 Beverley Campbell, Phenomenology as Research Method (Paper Victoria University of Technology), sebagaimana yang dimuat dalam http://www.socialresearchmethods.net/kb/qual.php akses tanggal 15 Oktober 2011, 10:22 WIB.
22 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
dianggap lumrah dalam kencenderungan pembangunan hukum di Sumatera Barat era otonomi daerah dan desentralisasi kekuasaan.
2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dokumen kebijakan Pemerintah Sumatera Barat pada era otonomi daerah. Kebijakan yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 jo. Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari. Evaluasi pelaksanaan Perda Nagari di Sumatera Barat diperoleh dari beberapa data statistik masyarakat Sumatera Barat. Data primer juga diperoleh dengan proses observasi dan wawancara. Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen atau publikasi ilmiah lainnya yang bersifat autoritatif dan relevan dengan tema yang dikaji dalam penelitian ini. Data sekunder yang dimaksud dapat berupa makalah-makalah yang disampaikan dalam musyawarah adat ataupun pemberitaan dalam media massa.
Dalam grounded theory, peneliti merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data, pengolahan data penyajian hasil penelitian.54 Oleh sebab itu, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode triangulasi teknik. Metode triangulasi teknik yang dipergunakan adalah menggabungkan pengumpulan dokumen, observasi partisipasi moderat dan wawancara tidak terstruktur (unstructured interview) terhadap purposive sample. Dokumen kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diperoleh dari salinan arsip resmi Perpustakaan DPRD Sumatera Barat. Data statistik perkembangan masyarakat Suamtera Barat diperoleh dari data yang dipublikasikan oleh BPS Provinsi Sumatera, BPS Nasional serta beberapa arsip mengenai realisasi APBD yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Sumatera Barat. Observasi partisipasi moderat dilakukan dengan cara mengamati Musyawarah Adat yang dilaksanakan pada bulan Maret 2012 di Solok. Dalam Musyawarah Adat tersebut, peneliti ikut serta dalam beberapa kegiatan namun tidak seluruhnya, sehingga terdapat keseimbangan antara kedudukan peneliti sebagai orang dalam dan sebagai orang luar dalam kegiatan tersebut. Wawancara tidak terstruktur dilakukan terhadap purposive
sample sebagai sumber data dengan beberapa pertimbangan tertentu. Purposive sample dalam penelitian ini adalah pemakalah dan sebagian Tokoh Adat yang terlibat dalam Musyawarah Adat. Sample tersebut
54 Sharan B. Merriam, Qualitative Research: a Guide to Design and
Implementation (San Fransisco: 2009, John Willey & Sons, Inc.), 29.
PENDAHULUAN | 23
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
dipilih dengan pertimbangan bahwa orang-orang tersebut dianggap tahu dengan fokus penelitian yang diinginkan.
3. Metode Analisis
Analislis dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis komparatif konstan (grounded theory research). Analisis ini dilakukan terhadap dua hal. Pertama, analisis terhadap perbandingan sistem pemerintahan nagari pada masa sebelum pemerintahan desa dan pada masa pemerintahan desa sehingga ditemukan konsep dasar sistem pemerintahan nagari pada masa otonomi daerah. Indikator yang dijadikan sebagai bahan perbandingan adalah terkait dengan masalah wilayah dan susunan pemerintahan yang terlibat di dalamnya. Kedua, analisis dilakukan terhadap data statistik terkait indikator perkembangan masyarakat dari tahun ke tahunnya. Data statistik yang dimaksud adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditentukan dari 4 variabel utama, yaitu: angka harapan hidup, tingkat melek huruf, lama masa sekolah dan pengeluaran perkapita.
G. Sistematika Penulisan
Penulisan karya ilmiah ini terdiri dari beberapa bab, antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berhubungan. Bab I merupakan bab pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab; pertama tentang latar belakang yang menunjukkan alasan mengapa pembahasan ini menjadi urgen untuk dibahas, kedua tentang identifikasi masalah, pembatasan masalah dan rumusan masalah, ketiga tentang tujuan penelitian, keempat tentang signifikasi penelitian, kelima tentang penelitian terdahulu yang relevan, keenam tentang metode penelitian, dan ketujuh tentang sistematika penulisan.
Bab II merupakan landasan teori. Bab ini menguraikan teori tentang sejarah panjang integrasi nilai adat dan Islam di Indonesia, sejarah masa pra kolonial, masa kolonial dan masa kemerdekaan hingga era reformasi. Bab III menguraikan geliat reformasi, desentralisasi dan otonomi daerah. Uraian ini dibagi menjadi beberapa sub bab, pertama tentang deskripsi kondisi sosial politik pemerintahan pusat dan kedua tentang tinjauan otonomi daerah dalam bingkai kebhinekaan di Indonesia.
Bab IV merupakan analisis terhadap temuan di lapangan. Pada bagian ini, diakukan analisis terhadap sistem pemerintahan nagari di Sumatera Barat. Analisis ini difokuskan pada beberapa hal pokok dalam pemerintahan nagari sebagaimana yang diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 1999 jo. Nomor 9 Tahun 2007. Substansi ini kemudian dikomparatifkan dengan sistem nagari yang sudah ada sebelumnya dan
24 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
juga sistem pemerintahan desa. Bab V merupakan analisis efektivitas pelaksanaan pemerintahan nagari di Sumatera Barat. Analisis efektivitas ini dilihat dari beberapa aspek utama, yaitu: pemekaran wilayah dan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, penyelesaian sengketa dan konflik serta peranan tokoh adat dalam pembangunan. Bab VI merupakan bab penutup. Bagian ini berisikan kesimpulan dan saran.
BAB II RELASI ISLAM DAN ADAT DI MINANGKABAU
Bagian ini merupakan penjabaran pola interaksi hubungan hukum adat dan hukum Islam yang sudah mulai sejak sebelum masa penjajahan. Pola hubungan antara hukum Islam dan hukum adat pada awalnya sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi pada masa itu. Persebaran dan adanya percampuran etnis berbagai suku bangsa yang didorong oleh motif ekonomi pada proses selanjutnya akan dihadapkan pada tingginya intensitas akulturasi kebudayaan dan juga ajaran keagamaan. Pola hubungan inilah yang kemudian dikembangkan dan beberapa kerangka teori dalam interaksi hukum adat dengan hukum Islam yang menjadi topik utama dalam bahasan tesis ini. Pada awalnya, antara hukum adat dan hukum Islam dipandang sebagai dua eksponen yang berbeda dan saling berlawanan. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh beberapa ahli Belanda pada masa kolonialisme Indonesia. Namun, perdebatan teori ini mengalami pergeseran yang signifikan pada era kemerdekaan.
Sepanjang sejarah, pada hakekatnya Islam senantiasa bersentuhan dengan budaya dan adat-istiadat masyarakat yang menjadi wadah aplikasi ajaran Islam itu sendiri. Pada awalnya, Islam bersentuhan dengan adat-istiadat masyarakat Arab. Setelah Islam berkembang keluar Jazirah Arab, maka Islam pun bersentuhan dengan budaya dan adat-istiadat di luar Jazirah Arab, seperti; Persia, Turki, Barbar, India dan Melayu.1 Demikian juga halnya dengan Indonesia. Indonesia mempunyai wilayah yang membentang dari Sabang sampai Merauke dengan luas wilayah sekitar 2.027.087 km2. Terdiri dari sekitar 13.578 pulau, 6.035 pulau sudah mempunyai nama dan 7.544 pulau belum mempunyai nama.2 Jumlah penduduknya sekitar 210 juta jiwa terdiri dari 177,53 juta jiwa menganut
1 Maidir Harun Dt. Sinaro, “Islam dan Budaya Minangkabau”, Menjadi
Indonesia: 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara, eds. Komaruddin Hidayat & Ahmad Gaus A.F., (Jakarta: Mizan, 2006), 203.
2 Hasan Shadily (ed.), Ensiklopedi Indonesia (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1982), jilid 3, 1418.
26 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
agama Islam.3 Indonesia mempunyai keberagaman kultur, budaya dan adat istiadat.
Sumatera Barat adalah salah satu dari sedikit daerah administratif setingkat provinsi di Indonesia yang teritorialnya identik dengan sebuah daerah budaya. Daerah budaya yang dimaksud adalah Minangkabau.4 Zaman sekarang, sebagian masyarakat mengidentikkan istilah Sumatera Barat dengan istilah Minangkabau. Namun apabila diamati dari perkembangan sejarah, wilayah Minangkabau tidak hanya meliputi Provinsi Sumatera Barat sekarang.5 Termasuk di dalamnya juga sebagian daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, bagian selatan Sumatera Utara, bagian barat daya Aceh dan bagian Negeri Sembilan di Malaysia. Kepulauan Mentawai yang secara administratif termasuk wilayah Sumatera Barat, tidak termasuk dalam bagian dari
3 Hasil sensus BPS pada tahun 2000 ini mengindikasikan bahwa berdasarkan
persentase sebanyak itu, secara faktual resmi, Islam adalah agama mayoritas yang dianut oleh warga Negara Indonesia. Bahkan tidak hanyak jumlah terbanyak dalam konteks Indonesia saja, jumlah ini merupakan persentase agama yang paling banyak dianut di antara bangsa-bangsa secara mondial. Leo Suryadinata, Penduduk Indonesia: Etnis dan
Agama dalam Era Perubahan Politik (Jakarta: LP3ES, 2003), 204. 4 Gusti Asnan, Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat Tahun 1950-an
(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 1. Istilah Minangkabau mengandung makna kebudayaan di samping makna geografis. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Minangkabau banyak dipahami sebagai sebuah suku bangsa dan bentuk kebudayaan. Sementara itu, masyarakat daerah ini tidak mengenal adanya istilah suku bangsa atau kebudayaan Sumatera Barat. Oleh sebab itu, tidaklah aneh ketika sebagian besar orang Minangkabau biasa menyebut dirinya dengan etnis Minangkabau dan bukan etnis Sumatera Barat. Amir Sjarifoedin, Minangkabau: Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain
Sampai Tuanku Imam Bonjol (Jakarta: Gria Media Prima, 2011), 2. Istilah Minangkabau berisikan pengertian kebudayaan yang tidak dikandung oleh istilah Sumatera Barat. Untuk keterangan lebih jauh, lihat penjelasan dan kronolgisnya dalam M. D. Mansoer, et. all., Sedjarah Minangkabau (Jakarta: Bhratara, 1970), 1-2.
5 Amir Sjarifoedin, Minangkabau, 1-2. Daerah Minangkabau lebih luas jika dibandingkan dengan daerah Provinsi Sumatera Barat saat ini. Sanusi Latief, “Gerakan Kaum Tua di Minangkabau” (Disertasi SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1987), 1. Lihat juga dalam M. D. Mansoer, et all,, Sedjarah Minangkabau, 1. Apabila ditinjau dari sudut sosial budaya, Minangkabau tidaklah identik dengan Sumatera Barat sekarang ini. Wilayah Minangkabau berada pada bahagian tengah pulau Sumatera, terdiri dari dataran tinggi yang subur di bagian timur Bukit Barisan. Sedangkan dataran rendahnya berada pada kawasan sekitaran daratan Riau dan Selat Malaka. Untuk lebih jelasnya silahkan simak peta alam Minangkabau dalam Elizabeth E. Graves, Asal-usul Elite Minangkabau
Modern: Respon Terhadap Kolonial Belanda Abad XIX-XX (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 16. Kajian mengenai wilayah Minangkabau klasik dapat ditemui dalam tambo Minangkabau.
RELASI ISLAM DAN ADAT DI MINANGKABAU | 27
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Minangkabau.6 Pergeseran pemahaman mengenai Minangkabau dan Sumatera Barat melalui rentetan proses dan kronologi yang panjang.
A. Masa Pra-Kolonialisme 1. Periode Minangkabau Timur (Abad VI - Pertengahan Abad ke-
XIV) Sejarah Indonesia dimulai sejak ditemukannya beberapa catatan
mengenai Indonesia pada abad ke-V M. Periode ini dikenal juga dengan masa proto sejarah Indonesia atau awal mula sejarah Indonesia.7 Sedangkan sejarah Minangkabau berdasarkan catatan-catatan tua dimulai pada abad ke-VII M. Penulisan sejarah Minangkabau pada masa awal sejarah ini sangat dipengaruhi oleh keberadaan tambo
8 dan kaba9 di
Minangkabau. Objektivitas dalam tambo dan kaba tidak sepenuhnya relevan dengan kebutuhan penulisan sejarah Minangkabau.10 Tambo dan
6 Hal ini disimpulkan setelah melihat pembagian daerah dalam penelitian yang
dilakukan oleh Edwin M. Loeb. Edwin M. Loeb tidak memasukkan kajian mengenai Kepulauan Mentawai dalam kajian Minangkabau. Pembahasan mengenai Kepulauan Mentawai dikaji dalam satu bab tertentu tentang pulau-pulau di sisi barat Sumatera. Lihat dalam Edwin M. Loeb, Sumatera: It’s History and People (Oxford: Oxford University Press, 1972), 97-127.
7 Sebelum menjadi bentuk Indonesia, gugusan kepulauan Indonesia sering kali dikenal dengan term nusantara. Nusantara pra-kolonial dalam beberapa literatur disebut juga dengan the lands below the wind (negeri di bawah angin). Jajat Burhanudin, Ulama
& Kekuasaan: Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia (Bandung: Mizan, 2012), 15.
8 Tambo (dalam KBBI diidentikkan dengan sejarah, babad, hikayat, riwayat kuno, uraian sejarah daerah yang seringkali bercampur dengan dongeng) merupakan uraian sejarah Minangkabau masa lalu yang seringkali bercampur dongeng. Amir Sjarifoedin, Minangkabau, 33. Secara sederhana, tambo dapat diidentikkan dengan historiografi tradisional asli milik masyarakat Minangkabau, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis. Gusti Asnan, Memikir Ulang Regionalisme, 8.
9 Kaba merupakan bentuk tambo yang diceritakan secara oral. Setelah masuknya Islam di Minangkabau dan mulai diperkenalkannya tradisi menulis dalam bahasa arab, maka tambo bertransmisi dari bentuk oral ke bentuk tertulis. Tambo-tambo yang pada awalnya dikabakan (dikabarkan) secara lisan kemudian dituliskan dalam aksara arab melayu. Amir Sjarifoedin, Minangkabau, 34.
10 Hal ini dikarenakan banyaknya tambo yang beredar di Minangkabau dengan berbagai versi yang terkadang terlihat saling berlawanan. Kekacauan logika dalam tambo ini juga pernah disinggung oleh A. A. Navis. Tidak hanya sebatas itu, penulisan sejarah Minangkabau pada masa awal sejarahnya sangat dipengaruhi oleh keberadaan mitos yang bersifat fiktif. Sebagaimana yang diungkapkan oleh M.O. Parlindungan, bahwa penulisan sejarah Minangkabau hanya 2% saja yang berdasarkan fakta, sedangkan 98% lagi merupakan mitos yang dipercayai secara turun temurun. Lihat dalam M. O. Parlindungan, Kata Sambutan, “Sedjarah Minangkabau”, eds. M. D. Mansoer, et. all. (Jakarta: Brathara, 1970), ix.
28 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
kaba yang beredar di Minangkabau bukanlah milik pribadi. Keberadaan tambo dan kaba yang tidak mempunyai otentisitas hak milik ataupun hak kekayaan intelektual, berakibat pada kemunculan beragam versi tambo dan kaba yang beredar di kalangan masyarakat. Hal ini juga menjadi semakin fiktif dikarenakan dalam uraian penjelasan tambo tidak menampilkan penanggalan dan kronologi kejadian secara rinci.11 Salah satu pendekatan yang dipergunakan untuk memberikan gambaran sejarah Minangkabau adalah penyelidikan terhadap perkembangan perekonomian dan perdagangan pada masa tersebut. Perkembangan perdagangan dan ekonomi mempunyai kaitan erat dengan ekspansi daerah Minangkabau dalam bentuk pembentukan daerah rantau.
Salah satu indikator yang bisa dipergunakan untuk menyelidiki kondisi perdagangan dan ekonomi adalah hasil bumi dan kondisi alam dari suatu daerah. Kelompok etnis Minangkabau, secara historis dan geografis dianggap sebagai komunitas yang menyerupai budaya pesisir. Padahal, kenyataannya masyarakat Minangkabau termasuk komunitas pedalaman. Hal ini dikarenakan secara geografis masyarakatnya banyak menempati daerah seputar pegunungan. Salah satu ciri masyarakat pedalaman adalah adanya kecenderungan menjadikan pertanian sebagai sumber penghidupannya. Akan tetapi, ciri tersebut tidak sepenuhnya melekat pada etnis Minangkabau. Dalam prespektif sejarah perdagangan,12 komunitas Minangkabau justru mempunyai peranan penting dalam perdagangan lada (merica) dibanding masyarakat pesisir.
Minangkabau merupakan jalur perdagangan penting, terutama karena letak geografisnya yang strategis di pesisir barat pantai Sumatera dan kesuburan tanahnya yang mengandung berbagai macam barang tambang dan menghasilkan komoditas.13 Berdasarkan catatan sejarah,
11 Meskipun demikian, Azyumardi Azra berhasil merasionalisasikan teori
hubungan penciptaan alam Minangkabau. Sebagaimana yang dijelaskan dalam tambo, dengan teori emanasi dalam filsafat Islam dan tasawuf. Analisis yang melakukan komparasi beberapa historiografi tradisional lainnya yang berada di luar Minangkabau, seperti Misa Melayu dan Hikayat Siak, mengarahkan pada satu kesimpulan bahwa Islam dibawa oleh kaum sufi dan terpengaruhi oleh konsepsi tasawuf. Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII: Akar
Pembaharuan Islam Indonesia (Jakarta: Kencana, 2013), Edisi Perennial, 33-36. 12 Amir Sjarifoedin, Minangkabau, 7. Secara historis, pulau Sumatera
merupakan pulau dengan penduduk yang gemar berdagang dan dinamis, sehingga menjadi arena percaturan politik dunia internasional atau persaingan prestasi individu. Orang Minangkabau di Sumatera Barat khususnya adalah pewaris terhormat dari tradisi yang sudah sangat tua ini. Elizabeth E. Graves, Asal-Usul Elite Minangkabau, 1.
13 Azyumardi Azra, Surau: Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan
Modernisasi (Jakarta; Logos, 2003), 32.
RELASI ISLAM DAN ADAT DI MINANGKABAU | 29
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
produsen dan penyalur lada sudah berkembang dengan pesat di pesisir barat pantai Sumatera sejak abad ke-VI M. Daerah rantau di Minangkabau dikenal sebagai daerah utama penghasil lada pada tahun 500 M. Daerah-daerah yang dimaksud adalah lembah aliran Batang Kampar Kiri dan Kampar Kanan serta lembah aliran Batanghari atau Sungai Dareh. Daerah inilah yang kemudian dikenal dengan Minangkabau Timur. Daerah inilah yang menjadi lokasi berkembangnya kerajaan-kerajaan lama, pusat perdagangan lada serta perkembangan ekonomi, politik dan budaya hingga pada pertengahan abad ke-XIV M.14
Pelayaran tradisional yang dilakukan pada masa itu sangat tergantung dengan kondisi alam dan iklim. Para pedagang yang berasal dari India, Persia dan Cina membutuhkan waktu satu tahun pelayaran untuk sampai ke pulau Sumatera. Di pulau Sumatera mereka menjual barang-barang mewah dan kembali pulang ke negaranya dengan membeli lada dari penduduk setempat. Panen lada yang hanya dilakukan setahun sekali memberikan banyak waktu luang bagi para saudagar tersebut. Banyak kegiatan yang dilakukan untuk menunggu waktu panen lada tiba. Salah satunya adalah bersosialisasi dengan masyarakat setempat. Sebagian besar pedagang yang berasal dari India menganut agama Budha (Hinayana) sehingga lambat laun agama tersebut berkembang dengan sendirinya di kalangan atas sebagai akibat dari adanya interaksi dengan masyarakat. Agama Budha inilah yang pertama kali berkembang di daerah Minangkabau Timur.15
Berdasarkan berita-berita lama Cina,16 disebutkan bahwa kerajaan Budha (Hinayana) mulai berkembang di pusat-pusat perdagangan lada. Muara Tembesi (Melayu Tua) merupakan Bandar utama di bagian utara.
14 M. D. Mansoer, et. all., Sedjarah Minangkabau, 40-41. 15 Secara lebih rinci, M.D. Mansur mengurutkan kronologis perkembangan dan
pengaruh agama pada masa Minangkabau tradisonal sebagai berikut; pertama, Budha Hinayana pada abad ke-VI-VII, kedua Islam Sunni antara tahun 670 M – 730 M, ketiga Budha Mahayana antara tahun 680 M – 1000 M dan keempat Islam Syiah antara tahun 1100 M – 1350 M. Penjelasan lebih lanjut bisa disimak dalam M. D. Mansoer, et. all., Sedjarah Minangkabau, 42-43.
16 Berita-berita lama Cina ini berasal dari catatan perjalanan seorang Pendeta Budha dari Cina bernama I Tsing yang melakukan perjalanan ke India pada tahun 671 M dan kembali ke Cina pada tahun 685 M. Salah satu hal yang menarik dalam catatannya adalah ketika berada di Ibukota Meloyue, di mana pada tengah hari, orang-orang setempat dapat menginjak bayangan kepalanya sendiri. Hal ini mengindikasikan mengenai lokasi keberadaannya yang berada di sekitar daerah khatulistiwa. Salah satu Candi Budha yang terkenal adalah Candi Muara Takus yang berada tidak jauh dari khatulistiwa yang bisa dijadikan sebagai petunjuk keberadaannya pada waktu itu. M. D. Mansoer, et. all., Sedjarah Minangkabau, 43.
30 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Sedangkan Muara Sabak (Sriwijaya Tua) merupakan bandar utama di bagian selatan.17 Berita-berita yang berasal dari awal abad ke-VII M menunjukkan bahwa saudagar-saudagar Cina dan Arab telah sampai di Minangkabau. Saudagar-saudagar Arab yang datang ke Indonesia sebelumnya singgah di Persia. Sementara pada abad ke-VII M, Persia sudah berada dalam daerah yang ditaklukkan oleh kerajaan Islam. Hal inilah yang menjadi alasan utama bagi beberapa pakar yang menyatakan bahwa Islam telah masuk ke Minangkabau Timur sejak abad ke-VII M.18
Pada pertengahan abad ke-VII M, Cina dikenal sebagai pemasok utama lada yang melakukan perdagangan sampai ke Damsyik, kota dagang terbesar di Timur Tengah. Jalur perjalanan perdagangan ini dikenal dengan jalur sutera. Pada masa ini juga terjadi dinamika politik yang luar biasa baik di Cina maupun di daerah Timur Tengah. Kerajaan Cina yang pada waktu itu dikuasai oleh Dinasti T’ang (607 M – 908 M) mempunyai kekuasaan sampai ke sebagian besar Asia Tengah. Pada saat yang hampir bersamaan,19 kekuasaan Khalifah Umayyah (660 M – 743 M)20 juga meliputi sebagian Asia Tengah hingga Iberia (732 M)21 dengan
17 Dalam catatan lama, disebutkan bahwa Sanfotsi merupakan bandar utama
yang dikujungi oleh para saudagar untuk membeli lada. Secara fonetis, kata san-fo-tsi dekat sekali dengan kata Zambesi. Sedangkan di Sriwijaya Tua dikenal juga bandar Muara Sabak yang dalam pemberitaan Arab disebut dengan zabag. Dalam pemberitaan Arab, Sriwijaya lazim juga disebut dengan sribuzza, sedangkan dalam pemberitaan Cina dikenal dengan chelifoche. M. D. Mansoer, et. all., Sedjarah Minangkabau, 43. Dalam naskah yang berjudul Chu-Fan-Chi karya Chau Ju-Kua tahun 1225, disebutkan bahwa negeri san-fo-tsi memiliki 15 daerah bawahan yang membentang dari bagian selatan Thailand, sebagian Trengganu, Selat Malaya, Pahang, sebagian Aceh, Jambi, Palembang dan Sunda. Istilah san-fo-tsi pada zaman Dinasti Song, sekitar tahun 950-an, identik dengan Sriwijaya. Meskipun Sriwijaya mengalami kekalahan pada tahun 1025, istilah tersebut masih tetap dipakai dalam beberapa naskah kronik Cina untuk menyebutkan pulau Sumatera secara umum. Amir Sjarifoedin, Minangkabau, 202.
18 M. D. Mansoer, et. all., Sedjarah Minangkabau, 45. 19 Lebih jauh lagi, al T}aba>ri menyatakan bahwa Qutaibah telah menakhlukkan
Kasygar di Turkistan Cina pada tahun 715 M, bahkan telah mencapai daerah Cina. Penjelasan tersebut mengindikan bahwa penakhlukkan yang sebenarnya dilakukan oleh Nashr ibn Sayyar dan penerusnya. Phillip K. Hitti, History of The Arabs (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), cet-2, 262.
20 Phillip K. Hitti, History of The Arabs, 235-278. Terdapat beberapa perbedaan pendapat terkait masa pemerintahan Umayyah, sebagian berpendapat dari tahun 661 M hingga 750 M, Marshall G. S. Hodgson, The Venture of Islam: Iman dan Sejarah dalam
Peradaban Dunia (Jakarta: Paramadina, 2002), 5. Sebagian lagi menyatakan sejak tahun 661 M hingga tahun 749 M, A. Syalabi, Sejarah dan Kebudayaan Islam (Jakarta: Alhusna Zikra, 1995), jilid 2, cet-3, 24-137, juga Ahmad al-Usairy, Sejarah Islam: Sejak
Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX (Jakarta: Akbarmedia, 2009), 179.
RELASI ISLAM DAN ADAT DI MINANGKABAU | 31
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
ibukota Damsyik. Pada saat itu, Damsyik merupakan pusat perniagaan, kegiatan politik dan kebudayaan terbesar di Timur Tegah. Keberadaan dua kerajaan besar yang berdampingan ini seringkali menimbulkan konflik dan peperangan.22 Ketegangan politik keduanya menjalar sampai ke Minangkabau Timur selaku pusat pengadaan lada. Kedua kerajaan besar ini ingin memonopoli lada dan menanamkan pengaruhnya di Minangkabau Timur.
Muawiyyah23 (661 M – 680 M) berusaha keras untuk menguasai perdagangan lada guna menjaga tersedianya pasokan lada sehingga tidak terlalu tergantung dengan Dinasti T’ang. Oleh sebab itu, bandar-bandar perdagangan Umayyah di Teluk Persia melakukan hubungan dagang dengan Minangkabau Timur. Para saudagar ini kemudian menjadi perantara Muawiyyah untuk menyampaikan surat kepada Raja Sriwijaya Tua pada waktu itu, yaitu Sri Maharaja Lokitawarman. Surat tersebut berisikan ajakan masuk Islam dan upaya menjalin hubungan dagang langsung dengan Damsyik.
Manuver politik Muawiyyah ini kemudian dilanjutkan oleh cucu beliau, Sulaima>n Abd al Ma>lik (714 M – 717 M) yang memerintahkan angkatan lautnya untuk menduduki dan memonopoli perdagangan lada di Muara Sabak. Sri Maharaja Srindrawarman selaku pengganti Sri Maharaja Lokitawarman masuk Islam pada tahun 718 M.24 Beliau mempunyai hubungan yang baik dengan Khalifah Umar ibn Abd Azi>z (717 M – 719 M).25 Pasca runtuhnya Dinasti Umayyah di Damsyik pada tahun 738 M, Andalusia (Spanyol) kemudian berkembang menjadi pusat kekuasaan Dinasti Abasiyyah (750 M – 1558 M).
Keberadaan jalur pelayaran langsung dari Minangkabau Timur ke Timur Tengah sangat merugikan Dinasti T’ang. Hal ini pada akhirnya
21 Penakhlukkan Iberia terjadi pada masa pemerintahan His}a>m ibn Abd Ma>lik
(723 M – 742 M). Ahmad al-Usairy, Sejarah Islam, 207-209. 22 Ketegangan-ketegangan dan pertempuran seringkali terjadi di daerah
Sinkiang yang penduduknya beragama Islam, namun berada di bawah kekuasaan Dinasti Cina. M. D. Mansoer, et. all., Sedjarah Minangkabau, 44.
23 Muawiyyah merupakan Khalifah pertama Dinasti Umayyah yang dinobatkan sebagai khalifah Iliya (Yerusalem) pada tahun 660 M. Phillip K. Hitti, History of The
Arabs, cet-2, 235. 24 M. D. Mansoer, et. all., Sedjarah Minangkabau, 45. 25 Hubungan yang baik di antara keduanya dibuktikan dengan korespondensi
yang kuat. Bukti surat ini dapat ditemukan di Museum Spanyol Kota Madrid. Surat-surat tersebut membuktikan bahwa ajaran Islam yang dikembangkan oleh Dinasti Umayyah telah masuk ke Minangkabau Timur sejak abad ke-VII M, bahkan telah ada raja dari kerajaan di Minangkabau yang masuk Islam pada abad ke-VIII M. M. D. Mansoer, et. all., Sedjarah Minangkabau, 45.
32 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
memicu keinginan Dinasti T’ang untuk memotong manuver politik yang sudah dilakukan oleh Khalifah Umaiyyah. Menaggapi hal tersebut, Dinasti T’ang mengirimkan 2 orang pendeta Budha Mahayana yang bernama Wajarabodhi dan Amoghabajra ke Sriwijaya Tua. Kedua pendeta ini bertugas untuk meruntuhkan ideologi Islam yang sudah dipeluk oleh masyarakat setempat dan mengembangkan ajaran Budha Mahayana.26 Guna menunjang usahanya ini, Dinasti T’ang mendirikan bandar untuk menguasai kembali perdagangan. Catatan I’tsing menyatakan bahwa intensitas usaha yang dilakukan oleh Dinasti T’ang ini berdampak pada adanya perubahan nama Moloyue (Sriwijaya Tua) menjadi Sriwijaya pada tahun 685 M.27 Hal yang menjadi catatan penting pada masa ini adalah garis pantai pada abad ke-VII M jauh berbeda dengan garis pantai pada saat sekarang. Pada masa ini, garis pantai dari pesisir Minangkabau Timur ke Sumatera Selatan masih berada dalam satu aliran sungai-sungai besar sebagai akibat dari endapan lumpur yang dibawa sepanjang tahun oleh aliran sungai-sungai tersebut.
Kerajaan Sriwijaya mengalami masa kemunduran karena adanya pertikaian agama antara Budha Hinayana dan Mahayana. Mahayana merupakan aliran Budha yang terbesar di Jawa, sedangkan Hinayana merupakan aliran Budha yang berkembang di Palembang.28 Persatuan kerajaan mulai melemah, sehingga Raden Wijaya dari Singosari menaklukkan Sriwijaya pada tahun 1275. Dikarenakan Sriwijaya tidak dibangun lagi, maka pusat kerajaannya dipindahkan ke hulu di antara Jambi dan Minangkabau sekarang dan diberi nama Dharmasraya.
2. Kerajaan Pagaruyung (1347 – 1809)
Kerajaan Pagaruyung bukanlah kerajaan Minangkabau. Kerajaan Pagaruyung merupakan kerajaan Melayu yang pernah berdiri meliputi Provinsi Sumatera Barat sekarang dan beberapa daerah di sekitarnya.29 Nama kerajaan Pagaruyung sendiri dirujuk dari tambo yang beredar dalam masyarakat Minangkabau sendiri yang pada awalnya merupakan nama sebuah nagari. Berdirinya Kerajaan Pagaruyung diawali dengan adanya ekspedisi pamalayu
30 yang terjadi pada tahun 1275 M.
26 M. D. Mansoer, et. all., Sedjarah Minangkabau, 45. 27 Hal ini diperkuat dengan berita yang dimuat dalam Prasasti Kedudukan Bukit
yang bertahunkan 605 Syaka atau 683 Masehi. M. D. Mansoer, et. all., Sedjarah
Minangkabau, 46. 28 Hamka, Islam dan Adat Minangkabau (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), 8-9. 29 Amir Sjarifoedin, Minangkabau, 199. 30 Merujuk pada Kidung Panji Wijayakrama dan Pararaton, pada tahun 1275,
Kertanegara mengirimkan utusan dari jawa ke Sumatera yang dipimpin oleh Mahisa
RELASI ISLAM DAN ADAT DI MINANGKABAU | 33
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Kemunculan Kerajaan Pagaruyung diawali dengan adanya ekspansi yang dilakukan oleh tentara dari Kerajaan Singosari yang dipimpin oleh Raja Kartanegara31 ke Malayu Jambi. Ekspedisi yang dilakukan Singosari ini berhasil menguasai Lembah Batanghari sampai ke Sungaidareh pada tahun 1275. Kemudian sampai ke daerah lembah Sungai Kampar Kiri dan Kampar Kanan pada tahun 1286. Di sisi lain, Stutterheim32 berpendapat bahwa ekspedisi Pamalayu tidaklah diidentikkan dengan penaklukan Kerajaan Melayu Jambi, melainkan upaya persekutuan di antara kedua kerajaan tersebut dengan mengadakan ikatan perkawinan.
Pasca takluknya Melayu Jambi di tangan Singosari, Melayu Jambi tidaklah mempunyai kebebasan untuk mengadakan ikatan perdagangan ke luar negeri. Hal ini dibuktikan dengan catatan lama Tionghoa tentang kedatangan seorang utusan Melayu ke Cina pada tahun 1281. Pada waktu itu, Cina diperintah oleh Kubilai Khan33 dari Dinasti Mongol yang pada tahun 1292 mengirimkan Armada Selatan untuk menghancurkan Singosari.34
Keberhasilan Singosari menguasai Melayu berimbas pada terjepitnya para pedagang Islam karena semakin berkembangnya ajaran Budha Tantrayana. Namun, pedagang Islam tidak mau berpangku tangan. Hal ini terbukti dengan adanya inisiatif untuk menggalang kerjasama dan meminta bantuan kepada Kubilai Khan untuk menghancurkan Singosari guna merebut kembali hak monopoli dagang merica. Perebutan daerah penghasil lada ini berlangsung terus menerus antara saudagar Islam yang berada di pantai timur Sumatera dengan kekuatan Budha Tantrayana dari
Anabrang atau Kebo Anabrang. Amir Sjarifoedin, Minangkabau, 203. Lihat juga dalam Edison M.S., et. all., Tambo Minangkabau: Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2010), 77.
31 Raja Kartanegara mempunyai beberapa tujuan politik pada masa pemerintahannya, yaitu; a) upaya konsolidasi politik dalam negeri; b) membentuk satu kekuatan politik di daerah-daerah luar Jawa guna mencapai hegemoni politik di Asia Tenggara; c) menguasai lautan guna memonopoli perdagangan, dan; d) menyebarluaskan ajaran Budha Tantrayana. M. D. Mansoer, et. all., Sedjarah Minangkabau, 52.
32 Keterangan lebih lanjut bisa ditemukan dalam W.F. Stutterheim, De
Dateering van Eenige Oost-Javaansche Beeldengroepen (Batavia: TBG deel LXXVI, 1936) sebagaimana yang dikutip oleh M. D. Mansoer, et. all., Sedjarah Minangkabau, 53.
33 Kubilai Khan merupakan cucu Genghis Khan yang mulai menebar ancaman ketika naik tahta pada tahun 1260 dan mendirikan Dinasti Yuan pada tahun 1280. Ancaman ini dimulai ketika Kubailai Khan meminta pengakuan kedaulatan atas daerah-daerah yang ditaklukkannya yang pada dekade sebelumnya telah mengakui raja-raja Cina dari Dinasti Sung. Amir Sjarifoedin, Minangkabau, 206.
34 M. D. Mansoer, et. all., Sedjarah Minangkabau, 53.
34 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Jawa Timur hingga masa Gajah Mada (1331-1365) dan Hayam Wuruk (1350-1387).35
Sejak tahun 1292, pengaruh Islam semakin kuat pada daerah-daerah penghasil lada di Sumatera sehingga Hindu Jawa tidak dapat berbuat banyak. Pada tahun yang sama, Jayakatwang dari Kediri berhasil meruntuhkan dan merebut kekuasaan Singosari. Hal ini serentak dengan berlabuhnya armada selatan dari Cina yang dikirim oleh Kubilai Khan. Kondisi ini menimbulkan kekacauan yang luar biasa. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Pangeran Wijaya untuk mendirikan kerajaan baru yang diberi nama Majapahit, selaku pelanjut dan ahli waris Singosari di segala bidang, termasuk masalah imperialisme ke daerah-daerah di luar Jawa.36
Hindu Jawa tidak bisa diam melihat semakin menguatnya pengaruh Islam di Sumatera dan bermaksud hendak melakukan penyerangan guna merebut kembali pusat-pusat perdagangan lada. Pada tahun 1339, Adityawarman dikirim sebagai uparaja atau raja bawahan Majapahit, sekaligus melakukan penaklukan yang dimulai dengan menguasai Palembang.37 Pada tahun 1347, Adityawarman yang dididik dan dibesarkan dalam lingkungan Kerajaan Majapahit memegang kekuasaan di lembah Batanghari. Ia kemudian menyatakan dirinya sebagai raja di Suwarnabhumi38 Sumatera yang pada awalnya berpusat di Sungailangsat, Sungaidareh, Rambahan dan Padangroco yang merupakan wilayah Minangkabau Timur dekat Batanghari.
Pada tahun 1349, Adityawarman berhasil menaklukan kerajaan Kuntu Kampar, sehingga Adityawarman menguasai seluruh daerah penghasil merica di Sumatera yang pada waktu itu merupakan rempah-rempah terpenting di seluruh dunia. Kerajaan yang didirikan oleh Adityawarman di pedalaman Sumatera Tengah menjadi cepat berkembang mengingat pentingnya merica dalam siklus perdagangan dunia. Adityawarman memindahkan pusat kerajaan dari Dharmasraya/
35 M. D. Mansoer, et. all., Sedjarah Minangkabau, 54. 36 M. D. Mansoer, et. all., Sedjarah Minangkabau, 55. 37 Kidung Pamacangah dan Babad Arya Tabanan menyebut nama Arya Damar
sebagai Bupati Palembang yang berjasa membantu Gajah Mada menaklukkan Bali pada tahun 1343. Menurut C. C. Berg, tokoh ini dianggap identik dengan Adityawarman. Amir Sjarifoedin, Minangkabau, 204.
38 M. D. Mansoer, et. all., Sedjarah Minangkabau, 55. Adityawarman memproklamirkan dirinya sebagai Maharajadiraja dengan gelar Srimat Sri Udayadityawarman Pratapaparakrama Rajendra Mauli Warmadewa dan menamakan kerajaannya dengan Malayapura. Kerajaan ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Melayu sebelumnya. Amir Sjarifoedin, Minangkabau, 204.
RELASI ISLAM DAN ADAT DI MINANGKABAU | 35
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Jambi ke pedalaman Sumatera39 karena didorong oleh keinginan mendirikan sebuah kerajaan yang terlepas dari pengaruh kekuasaan Majapahit.
Keinginan dan tindakan Adityawarman yang ingin melepaskan diri dari Majapahit tidak disetujui oleh Majapahit. Pada tahun 1409, Majapahit mengirimkan tentara untuk menundukkan raja keturunan Adityawarman. Akan tetapi usaha tersebut gagal karena tentara Minangkabau berhasil mengalahkan tentara Majapahit dalam pertempuran di Padang Sibusuk. Tentara inilah utusan terakhir dari Hindu Jawa yang datang ke wilayah Alam Minangkabau. Tidaklah mengherankan apabila Minangkabau dapat mengalahkan Majapahit dalam pertempuran bersenjata. Hal ini dikarenakan sejak tahun 1349 kerajaan yang didirikan oleh Adityawarman sudah mempunyai kedudukan yang kuat40 mengingat wilayah kekuasaannya pada sebagian besar Sumatera dan Semenanjung Malaka. Sistem pemerintahan yang digunakan pada waktu itu adalah sentralistis dengan kekuasaan tertinggi berada pada satu orang raja.41
Adityawarman merupakan tokoh penting dalam sejarah Minangkabau, yang memperkenalkan sistem pemerintahan kerajaan. Kontribusinya cukup besar dalam pengembangan agama Budha Minangkabau.42 Setelah memindahkan ibukota kerajaan ke pedalaman, Adityawarman menyusun sistem pemerintahan Pagaruyung mirip dengan sistem pemerintahan Majapahit pada masa itu. Sekaligus menyesuaikannya dengan karakter dan struktur kekuasanaan Kerajaan Dharmasraya dan Sriwijaya yang pernah dipakai masyarakat setempat. Dalam menjalankan pemerintahannya, Adityawarman dibantu oleh Datuk
39 Walaupun Ibukota Kerajaan Melayu telah dipindahkan ke pedalaman, namun
Dharmasraya masih tetap dipimpin oleh seorang Maharaja Dharmasraya yang berubah statusnya menjadi raja bawahan, sebagaimana yang diungkapkan dalam Kitab Undang-undang Tanjung Tanah di Kerinci yang diperkirakan pada masa Adityawarman. Amir Sjarifoedin, Minangkabau, 204.
40 Kekuasaan pemerintah Kerajaan Minangkabau pada periode 1349-1409 dibuktikan dengan keberadaan beberapa prasasti pada masa itu. Prasasti-prasasti tersebut adalah sebagai berikut; a) Prasasti Kubu Rajo 1349; b) Prasasti Pagaruyung 1357; c) Prasasti Saruaso I 1357; d) Prasasti Bandar Bapahat, dan; e) Prasasti Saruaso II. M. D. Mansoer, et. all., Sedjarah Minangkabau, 61-62.
41 Keterangan lebih lanjut bisa disimak dalam Amir Sjarifoedin, Minangkabau, 214-216.
42 Hal ini dibuktikan dengan adanya nama beberapa nama nagari yang berbau budaya Budha atau Jawa, seperti; Saruaso, Pariangan, Padang Barhalo, Candi, Biaro, Sumpur dan Selo. Amir Sjarifoedin, Minangkabau, 215.
36 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Parpatih Nan Sabatang dan Datuk Katumanggungan dalam jabatan yang setara dengan seorang senopati di Jawa.
Pemerintahan Adityawarman di Kerajaan Pagaruyung menerapkan sistem autokrasi dan demokrasi.43 Menurut tambo, kekuasaan Adityawarman hanya terbatas pada daerah Pagaruyung, sementara itu daerah lain di Minangkabau tetap di bawah pengawasan Datuk Katumanggungan dan Datuk Parpatih Nan Sabatang dengan pemerintahan adatnya. Dengan demikian, Adityawarman dianggap sebagai lambang kekuasaan saja, namun kekuasaan sesungguhnya berada di tangan Datuk Katumanggungan dan Datuk Parpatih Nan Sabatang.44 Kehidupan sosial masyarakat pada waktu itu diatur oleh tatanan adat Budi Caniago dan Koto Piliang.45
Perkembangan Islam pada abad XV membawa pengaruh terhadap Kerajaan Pagaruyung, terutama berkaitan dengan sistem patrilineal dan memunculkan fenomena yang relatif baru pada masyarakat di pedalaman Minangkabau. Perkembangan Islam di Minangkabau pada abad XVI46 melalui musafir dan guru-guru agama yang datang atau singgah dari Aceh dan Malaka. Salah satu murid ulama Aceh yang terkenal, Shekh Abdurrauf Singkil (Tengku Syiah Kuala) adalah Shekh Burhanuddin Ulakan yang aktif menyebarkan ajaran Islam di Minangkabau. Pada abad ke-XVII kerjaan Pagaruyung berubah menjadi Kesultanan Islam.
Adityawarman meninggal dunia pada tahun 1375.47 Berita tentang kematian Adityawarman tidak diikuti dengan penjelasan mengenai penyerahan kekuasaan pada waktu itu. Namun dalam beberapa dekade
43 Datoek Toeah, Tambo Alam Minangkabau (Bukittinggi: Pustaka Indonesia,
1976) sebagaimana yang dikutip dalam Amir Sjarifoedin, Minangkabau, 215-216. 44 Bahkan dalam tambo Minangkabau dinyatakan bahwa Adityawarman,
meskipun seorang raja yang besar pada waktu itu, namun ia tetap saja dianggap seorang sumando (=semenda) di Minangkabau yang mempunyai kekuasaan terbatas. Amir Sjarifoedin, Minangkabau, 216.
45 Mochtar Naim, Merantau: Pola Migrasi Masyarakat Minangkabau (Yogyakarta: Gajam Mada University Press, 1979), 20.
46 Sebelum abad XVI, beberapa bukti yang tidak lengkap menunjukkan bahwa penyeberan Islam bermula dari kepulauan bagian barat. Akan tetapi, tidak terlihat bahwa telah terjadi gelombang perkembangan Islam secara berkesinambungan ke daerah tetangganya. Bukti ini hanya memberi gambaran singkat mengenai proses yang berlangsung, meskipun proses yang berlangsung itu sangat rumit dan lamban. M. C. Ricklefs, A History of Modern Indonesia Since c. 1200 (Jakarta: Serambi, 2001), ed-3, 33.
47 M. D. Mansoer, et. all., Sedjarah Minangkabau, 62., lihat juga dalam Amir Sjarifoedin, Minangkabau, 226.
RELASI ISLAM DAN ADAT DI MINANGKABAU | 37
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
setelah itu disebutkan bahwa Minangkabau dipimpin oleh Sultan Alif48 yang beragama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Kerajaan Minangkabau sudah tidak lagi menganut ajaran Hindu, melainkan sudah menganut ajaran Islam dalam kerajaannya. Pada era ini, kerajaan Pagaruyung berubah menjadi Kesultanan Pagaruyung. Gelar yang diberikan kepada raja pun berubah menjadi sultan.49
Kekuatan pemerintahan pada masa Sultan Alif sudah mulai melemah. Hal ini dikarenakan sudah mulai terpecahnya daerah ke dalam beberapa pemerintahan sendiri, sehingga sistem pemerintahan sentralistis tidak belaku lagi. Hal ini terbukti dengan berdirinya kerajaan Pagaruyung di daerah pesisir yang mengakui dominasi politik ekonomi Aceh karena perdagangan di pesisir pantai sudah dikuasai oleh Aceh. Kerajaan Pagaruyung Minangkabau tidak mempunyai kekuatan perang seperti halnya beberapa kerajaan Islam lainnya, seperti Aceh, Demak, Banten, dan lain-lain yang segera membentuk angkatan perang setelah menganut ajaran Islam. Sistem pemerintahan yang dipakai adalah bentuk pemerintahan nagari yang dikepalai oleh Penghulu yang juga mengurus hubungan antar sesama nagari. Masing-masing nagari mempunyai hukum dan peraturannya masing-masing. Hukum yang dimaksud bukanlah hukum tertulis, melainkan hukum tidak tertulis yang diwariskan secara turun temurun melalui petatah-petitih. Rakyat sangat patuh pada Penghulu yang memegang adat secara teguh.
Pemerintahan pada masa ini bercorak desentralistis yang didasarkan pada aturan adat dan aturan Islam.50 Kekuasaan tidak lagi dipegang oleh satu orang saja, namun bentuk pemerintahan pada masa ini dikenal dengan istilah tungku nan tigo sajarangan atau dalam istilah lain disebut dengan tali tigo sapilinan. 51 Meskipun pada masa pemerintahan
48 Sejarah Minangkabau mengenal dua nama Alif yang hidup pada masa yang
berbeda, yaitu pada abad ke-16 dan abad ke-17. Firdaus, “Adat dan Islam: Proses Pembentukan Hukum Islam di Minangkabau”, dalam Mozaik Islam Nusantara: Seri
Agama, Budaya dan Negara, eds. Nurus Shalihin, et. all. (Padang: Imam Bonjol Press, 2013), 52. Sultan Alif yang disebutkan dalam kajian ini adalah Sultan Alif yang memerintah di Minangkabau pada abad ke-16.
49 Masa Pemerintahan Sultan Alif dimulai sejak sekitar tahun 1560 M. M. D. Mansoer, et. all., Sedjarah Minangkabau, 63.
50 Amir Sjarifoedin, Minangkabau, 226. 51 Term tungku nan tigo sajarangan merupakan penggambaran urgensi akan
fungsi dari masing-masing pemuka nagari dalam manjalankan perannya dalam pemerintahan. Tungku yang dimaksudkan di sini menggambarkan morfologi tungku/kompor tradisional yang disusun dari 3 batu besar yang di atasnya diletakkan wadah untuk memasak, seperti periuk atau kuali. Tiga batu tersebut mendeskripsikan tiga tokoh utama dalam masyarakat, yaitu; penghulu, alim ulama dan cadiak pandai
38 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Sultan Alif sudah ada daerah yang memisahkan diri, seperti Indrapura, atau daerah yang duduki oleh Aceh seperti Pariaman, Tiku dan lain-lain, kekuasaannya meliputi; Kuantan, Cerati, Baserah, Kudaman, Panyian, lima kota (Seberahan, Semendalak, Banai, Kapak dan Teluk Kari), empat kota hilir (Kerasik Tawar, Gunung Ringin, Lubuk Jambi dan Sungai Pinang), dan dua kota (Lubuk Ambacang dan Sungai Manan). Daerah lain yang tunduk di bawah kekuasaan Minangkabau adalah; Siak, Indragiri, Jambi, Batanghari, Sungai Pagu, Pasaman dan Rao. Nagari-nagari yang beragam ini memerankan dirinya sebagai kesatuan yang merdeka, seperti halnya republik-republik kecil yang otonom,52 juga ada wilayah yang tergabung dalam entitas geografis dan politis di bawah Raja Pagaruyung.
Raja Pagaruyung dalam menjalankan pemerintahannya dibantu oleh rajo adat (raja yang berkuasa dalam bidang adat) dan rajo ibadat (raja yang berkuasa di bidang agama).53 Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa rajo adat dan rajo ibadat mewakili dua sub-divisi geografis yang utama dalam kerajaan, atau keduanya tidak lebih dari simbol kosmologis aturan alam Minangkabau.54 Meskipun demikian, hal ini menggambarkan bahwa tatanan masyarakat Minangkabau pada era Kerajaan Pagaruyung sudah tersusun secara sistemis.
B. Masa Kolonialisme 1. Awal Kedatangan Bangsa Asing
Meskipun hanya sedikit pengetahuan tentang Minangkabau pada abad XVI, konversi Minangkabau ke dalam Islam tampaknya dimulai sekitar abad XVI dan terjadi melalui pesisir barat dan pesisir timur.55 (cendikiawan). Konsep pemerintahannya digambarkan sebagai tali tigo sapilinan. Maksudnya, tiga tokoh ini dalam pemerintahan menjalankan tugasnya secara bersama-sama, saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, meskipun mereka mempunyai latar belakang yang jauh berbeda.
52 Elizabeth E. Graves, Asal-usul Elite Minangkabau, 35. 53 Konsep kepemimpinan formal ini dikenal dengan istilah Pimpinan Tigo Selo.
Raja Alam berkedudukan di Pagaruyung, Raja Adat berkedudukan di Buo dan Raja Ibadat berkedudukan Sumpur Kudus. Hal yang menarik untuk diperhatikan pada masa ini adalah kedudukan seorang Rajo Ibadat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kerajaan Pagaruyung telah memasukkan Islam sebagai salah satu bagian dari tugas pemerintahan. Maidir Harun Dt. Sinaro, “Islam dan Budaya Minangkabau”, 208.
54 William Marsden, The History of Sumatera (London: J. Mc. Creery, 1811), 282-283, P.E. de Josselin de Jong, Minangkabau and Negeri Sembilan: Socio-Political
Structure in Indonesia (Jakarta: Brathara, 1960), 107-111, Elizabeth E. Graves, Asal-
usul Elite Minangkabau, 35. 55 Cristine Dobbin, “Islamic Revivalism in Minangkabau at the Turn of
Nineteenth Century”, Modern Asian Studies, 8 (1974), 324 dalam Azyumardi Azra, Surau, 42. Lihat juga dalam Audrey Kahin, Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatera
RELASI ISLAM DAN ADAT DI MINANGKABAU | 39
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Bandar pelabuhan merupakan lokasi strategis dalam awal penyebaran Islam di Minangkabau. Malaka mulai dikuasai Potugis pada tahun 1511.56 Sementara Minangkabau masih tetap dengan keadaannya yang dulu. Pasca jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, Aceh mulai memulihkan kebesarannya kembali dan menentang Portugis. Pada awalnya pusat kesultanan dipindahkan ke Pidie dan akhirnya ke Aceh Besar.57 Antara Aceh dan Portugis terdapat persaingan dalam hal perniagaan di pantai barat Sumatera yang memaksa Aceh menaklukkan daerah-daerah yang berada di garis pantai barat Sumatera. Keberhasilan Portugis merebut Malaka menimbulkan reaksi yang luar biasa dari kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Tujuan utama Portugis merebut Malaka adalah untuk kepentingan niaga dan penyebaran agama Kristen.
Ekspansi teritorial yang dilakukan Aceh ke pesisir barat dan timur pulau Sumatera berlangsung sejak masa pemerintahan Sultan Alaudin
Riayatshah al Qahha>r (1539-1571) dan mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Di daerah-daerah yang berada di pesisir barat pantai Sumatera, yang berada dalam wilayah pesisir Minangkabau dalam bentuk nagari-nagari kecil otonom58 seringkali terjadi konflik antar sesamanya karena kurangnya koordinasi yang baik. Hal ini jelas saja memudahkan usaha Aceh untuk semakin meluaskan dominasi politik dan ekonominya. Apalagi didorong oleh
Barat dan Politik Indonesia 1926-1998 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 6. Hal yang sama juga diungkapkan oleh beberapa literatur lain seperti Tome Pires, The Suma
Oriental of Tome Pires, an Account of the East, from the Red Sea to the Japan, Written
in Malacca and India in 1512-1515, ed. Armando Cortesão (New Delhi: Asian Educational Service, 1990), 164 dan Thomas Dias, “A Mission to the Minangkabau King”, dalam Witness to Sumatera: A Traveller’s Anthology, ed. Anthony Reid (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1995), 152-161. Uraian lebih lanjut lihat dalam Jeffrey Hadler, Sengketa Tiada Putus: Matriarkat, Reformisme Islam dan Kolonialisme
di Minangkabau (Jakarta: Freedom Institute, 2010), 32. Lihat juga ulasan mengenai analisis Pires yang berkaitan dengan ini dalam M. C. Ricklefs, A History of Modern
Indonesia, 34-37. 56 Setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, Kesultanan Aceh tampil
mengambil peran penting dalam partisipasi nusantara dalam perdagangan rempah-rempah di Lautan India. Hingga pada abad ke-XVI partisipasi Aceh dalam perdagangan di Lauran India mencapai puncak kejayaannya. Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur
Tengah, 40. 57 Hamka, Islam dan Adat, 11. 58 Pada dasarnya, daerah-daerah ini merupakan penghasil lada dan emas yang
mempunyai kedudukan penting dalam perkembangan ekonomi dunia pada masa itu. Daerah yang dimaksud adalah Barus, Natal dan Pasaman, Bandar Tiku, Pariaman, Pauh, Teluk Bungus, Tarusan dan Teluk Ketaun. M.D. Mansoer, et. all., Sedjarah
Minangkabau, 77-79.
40 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
keinginan untuk menguasai hasil bumi guna menutupi biaya perang dengan Portugis yang berlangsung terus menerus. Sultan Alaudin
Riayatshah al Qahha>r menunjuk salah seorang putranya untuk menjadi Panglima Syahbandar di Pariaman. Ia giat sekali mengembangkan ajaran Islam dengan membuka pesantren di Ulakan Pariaman. Ia kemudian dikenal dengan Shekh Burhanuddin,59 Tuanku Ulakan. Beliau hidup dan sangat dihormati di Minangkabau dan dianggap sebagai tokoh yang paling berpengaruh dalam pengembangan Islam di Minangkabau.
Kekayaan alam Minangkabau terutama daerah pesisir berada dalam dominasi politik Aceh sejak pertengahan abad XVI. Hal ini membuat Islam semakin berkembang dan mempunyai kedudukan yang kuat di daerah pesisir. Kondisi ini semakin diperkuat dengan adanya usaha yang dilakukan oleh Shekh Burhanuddin dalam mengembangkan ajaran Islam. Puncaknya adalah dengan masuk Islam-nya Sultan Muhammad Alif pada penghujung abad XVI.60 Meskipun demikian, pada dasarnya masyarakat Minangkabau secara individual tidaklah dikatakan baru pertama kali disentuh oleh Islam. Daerah rantau Minangkabau Timur sudah disentuh oleh para saudagar Islam mengingat posisinya selaku pusat perniagaan lada terbesar pada abad VI dan VII. Bahkan pada abad VIII sudah ada Raja Minangkabau Timur yang memeluk Islam. Hanya saja, penyebaran Islam secara intensif61 di Minangkabau baru terjadi pada abad XVI.62 Masuknya Islam pada masa ini bukanlah dari daerah rantau
59 Sejarah perkembangan Islam di Minangkabau mengenal adanya 2 orang
Shekh Burhanuddin. Pertama, Shekh Burhanuddin Kuntu yang meninggal pada tahun 1214 M. Shekh Burhanuddin Kuntu datang dari Arab dan menyebarkan agama Islam di Aceh dan kemudian di Minangkabau (Batu Hampar, Bonjol, Ulakan dan Kuntu Kampar Kiri). Kedua, Shekh Burhanuddin Ulakan yang lahir pada tahun 1641 M. Islam yang dikembangkan Shekh Burhanuddin Ulakan adalah Islam dalam bentuk Tarekat Shatariyah. Lihat dalam Amir Sjarifoedin, Minangkabau, 367-412., lihat juga dalam Oman Fathurrahman, Tarekat Syatariyah di Minangkabau (Jakarta: Prenada Media Group bekerjasama dengan École Française d’Extrême-Orient, PPIM UIN Jakarta dan KITLV, 2008), 35.
60 M. D. Mansoer, et. all., Sedjarah Minangkabau, 80. 61 Sedikit berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Yaswirman, Shekh
Burhanuddin mempunyai peranan penting dalam pengembangan Islam di Minangkabau. Meskipun pada masa-masa sebelumnya Islam sudah mulai bersentuhan dengan masyarakat Minangkabau, namun belum begitu efektif dan frontal. Pengembangan Islam yang lebih efektif dan terbuka baru terlihat pada era Shekh Burhanuddin ini. Penjelasan lebih lanjut silahkan simak dalam Yaswirman, “Hukum Kekeluargaan Adat dan Hukum Kekeluargaan Islam di Indonesia” (Desertasi SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1997), 104.
62 Hal ini terbukti dengan pengakuan Kerajaan Pagaruyung terhadap kedaulatan Kesultanan Aceh pada awal abad XVII dan pengakuan terhadap kedudukan para
RELASI ISLAM DAN ADAT DI MINANGKABAU | 41
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Minangkabau Timur lagi, melainkan berkembang dari daerah pesisir barat.
Adanya hubungan batin yang kuat antara Minangkabau dengan Aceh diawali dengan adanya dominasi Aceh di wilayah Minangkabau. Namun, kebiasaan merantau masyarakat Minangkabau juga merupakan salah satu faktor pendukung semakin berkembangnya Islam di kalangan masyarakat Minangkabau. Perantau Minangkabau didorong oleh motif ekonomi dan keinginan untuk menuntut ilmu. Aceh, yang pada masa itu merupakan poros perkembangan Islam, menjadi salah satu tempat untuk menimba ilmu agama. Tidak hanya terbatas sampai di situ, kendala transportasi pada masa itu juga menjadi salah satu motor penggerak mobilisasi masyarakat Minangkabau ke Aceh. Masyarakat yang hendak menunaikan ibadah haji pada waktu itu harus ke Aceh dulu untuk bisa melanjutkan perjalanan ke Mekah. Hal ini dikarenakan pada waktu itu Aceh menguasai perniagaan dengan bandar perdagangan yang sangat ramai dilalui oleh lalu lintas kapal layar.63
Dominasi Aceh selama kurang lebih satu abad di daerah pesisir barat Minangkabau berimbas pada adanya akulturasi budaya Aceh dengan budaya setempat. Salah satu buktinya adalah mulai dipergunakannya aksara arab melayu dalam penulisan karya-karya sastra. Di samping nilai-nilai positif, ada juga beberapa efek negatif yang berkembang seiring dengan dominasi tersebut. Semakin banyaknya keturunan Aceh yang berkembang di daerah pesisir juga menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya perpecahan dalam nagari-nagari di pesisir Minangkabau.
Malaka jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1641. Pasca jatuhnya Malaka ke tangan Belanda, Belanda mengalihkan jalan dagang melalui pesisir barat Sumatera dan Selat Sunda. Pada saat yang bersamaan, Belanda juga mendirikan kantor dagangnya dari Indrapura sampai Salido.64 Secara langsung politik ini sangat merugikan Aceh sampai pada akhirnya perekonomian Aceh yang terpencil menjadi semakin lemah. Hal ini meningkatkan pamor kekuatan Belanda sampai berhasil menjadikan Batavia sebagai pusat kekuatan ekonomi, politik dan maritimnya se-Asia Tenggara pada tahun 1619.
Pada tahun 1665, masyarakat Minangkabau di pesisir barat Sumatera bangkit dan mengadakan pemberontakan terhadap Gubernur Gubernur Aceh di daerah pesisir barat pantai Sumatera. Amir Sjarifoedin, Minangkabau, 226.
63 Penjelasan lebih lanjut dapat ditemukan dalam M. D. Mansoer, et. all., Sedjarah Minangkabau, 80-84.
64 Hal ini dilanjutkan dengan pembangunan kantor dagang di pulau Cingkuak pada tahun 1664 untuk melawan Kesultanan Aceh. Amir Sjarifoedin, Minangkabau, 305.
42 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Aceh. Bahkan untuk melepaskan diri dari cengkraman Aceh, Belanda mengadakan perjanjian dengan Kerajaan Pagaruyung. Isi perjanjian tersebut adalah pemberian kebebasan kepada Belanda untuk mengadakan perdagangan di daerah pantai barat Sumatera. Perjanjian tersebut dilakukan oleh pihak Belanda dengan Sultan Ahmad Shah pada tahun 1668.65
Jauh berbeda dengan masa dominasi politik dan ekonomi Aceh, masa pendudukan Belanda di daerah pesisir selama kurang lebih dua abad tidak begitu banyak mempengaruhi kebudayaan Minangkabau. Mayoritas orang Belanda yang menetap dan berdagang di Aceh bukanlah kaum terpelajar dan hanya mempunyai fokus pada usaha meraih untung yang tinggi dengan usaha berdagang merica. Hal ini jelas saja tidak mempengaruhi kehidupan sosio-religius masyarakat setempat.66 Ditambah lagi anggapan kafir yang diberikan oleh masyrakat religius Minangkabau terhadap orang-orang Belanda dengan kebiasannya meminum minuman keras dan bermabuk-mabukan. Sebaliknya, Belanda memandang rendah masyarakat Minangkabau dengan agama yang dianutnya. Pengaruh yang timbul dengan pendudukan Belanda di pesisir barat pantai Sumatera hanyalah pada peralatan yang dipergunakan sehari-hari dan gaya berpakaian masyarakat setempat pada acara-acara adat dan lain sebagainya.67
Pola hubungan antara adat dan Islam mulai terlihat pada masa ini. Dalam konteks keindonesiaan, hukum Islam pernah dianut dengan sepenuhnya oleh masyarakat Islam. Meskipun masih didominasi oleh mazhab Sha>fii karena dianggap lebih dekat dengan kultur Indonesia pada waktu itu.68 Hukum adat setempat dalam perkembangannya seringkali menyesuaikan diri dengan dengan hukum Islam. Demikian juga halnya dengan hukum Islam yang juga bisa beradaptasi dengan kondisi hukum adat.69 Hal ini menunjukkan suatu kondisi bahwa sudah ada pola
65 Amir Sjarifoedin, Minangkabau, 306. 66 Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan keseharian masyarakat Minangkabau.
Pada masa dominasi Aceh, masyarakat Minangkabau mengalami akulturasi budaya yang sangat signifikan. Hal ini terbukti dengan mulai digunakannya budaya menulis dengan aksara arab yang disederhanakan ke dalam bentuk aksara arab melayu. M. D. Mansoer, et. all., Sedjarah Minangkabau, 113.
67 M. D. Mansoer, et. all., Sedjarah Minangkabau, 114. 68 Abdurrahman Wahid, Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia (Bandung:
Remaja Rosda Karya, 1991), 229. 69 Muhammad Adil, “Simbur Cahaya: Studi Tentang Pergumulan Hukum Islam
dan Hukum Adat dalam Kesultanan Palembang Darussalam” (Disertasi SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 2009), 53.
RELASI ISLAM DAN ADAT DI MINANGKABAU | 43
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
hubungan akomodasi yang terbentuk antara Islam dengan hukum adat setempat.
Berdirinya pemerintahan Belanda pada akhir abad XVII pada kenyataannya tidak terlalu mempunyai pengaruh terhadap hukum yang hidup di kalangan masyarakat pribumi. Teori receptie in complexu yang dimunculkan oleh van den Berg didasarkan pada kenyataan yang terjadi di Indonesia.70 Teori ini menyatakan bahwa bagi penduduk Indonesia berlaku hukum agamanya masing-masing, bagi penganut agama Budha berlaku hukum agama Budha, bagi penganut agama Kristen berlaku hukum agama Kristen dan begitu juga bagi pemelik agama Islam berlaku hukum Islam.71 Hal ini terlihat pada beberapa regulasi yang ditetapkan dalam rentang waktu tersebut. Salah satu contohnya adalah Statuta Batavia Tahun 1642 yang menyatakan bahwa sengketa waris antara orang pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam sebagai hukum yang dipakai sehari-hari.72
Pada awal kekuasaannya, rezim Belanda memilih untuk tidak ikut campur dengan institusi hukum Islam. Hukum keluarga Islam, terutama peraturan-peraturan yang menyangkut masalah perkawinan dan kewarisan, secara umum diaplikasikan.73 Meskipun demikian, sebuah perubahan mucul pada 25 Mei 1760 ketika VOC mengundangkan Resolutie der Indische Regeering (Resolusi Pemerintahan Hindia Belanda) yang juga dikenal dengan sebutan Compendium Freijher
74 (Koleksi Hukum Freijher). Resolusi ini merupakan peraturan yang pertama kali terbit dan berisikan kompilasi hukum Islam mengenai
70 Sebelum Hurgronje datang ke Hindia Belanda, hukum Islam dipahami
sebagai hukum pribumi, sebagai hukum adat. Berdasarkan hal ini, van den Berg memperkenalkan teori receptie in complexu. Menurutnya, agama-agama yang ada berpengaruh pada hukum adat, sehingga hukum adat ini hampir tidak ada lagi. Ahmad Baso, Islam Pasca-Kolonial: Perselingkuhan Agama, Kolonialisme dan Liberalisme (Bandung: Mizan, 2005), 275.
71 Teori van den Berg ini kemudian dikutip ulang oleh van Vollenhoven. Keterangan lebih lanjut dapat ditemukan dalam C. van Vollenhoven, Orientasi Dalam
Hukum Adat Indonesia (Jakarta: Djambatan, 1981), 15-16. Teori van Vollenhoven ini kemudian mendorong terbentuknya Staatsblaad Tahun 1882 Nomor 152 tentang Peradilan Agama.
72 Muhammad Daud Ali, “Hukum Islam: Peradilan Agama dan Masalahnya”, Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek, ed. Tjun Surjaman (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), 229.
73 Sajuti Thalib, Receptio A Contrario (Jakarta: Academica, 1980), 15-17. 74 Disusun oleh D.W. Freijer yang berisikan hukum perkawinan dan kewarisan
Islam yang telah direvisi dan disempurnakan oleh para penghulu. Muhammad Adil, “Simbur Cahaya”, 54.
44 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
perkawinan dan kewarisan sebagaimana yang diaplikasikan dalam Pengadilan VOC.75
Pada permulaan abad ke-XIX mulai bermunculan sikap-sikap curiga dari beberapa pejabat kolonial. Salah satunya adalah nasehat yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung Belanda bernama Scholten van Oud Harlem bahwa diharapkan agar pemerintah berhati-hati dalam dalam menerapkan hukum. Meskipun demikian, sejauh ini beliau tetap mengungkapkan bahwa merujuk kepada pasal 75 Regeering Reglement 1854, bagi kaum muslimin tetap diberlakukan hukum agamanya. Bahkan, lebih jelas lagi Salomon Keyzer dan van den Berg menyatakan bahwa penerapan hukum harus sesuai dengan agama yang dianut oleh seseorang.76 Kegagalan pemerintah Belanda dalam menerapkan regulasi yang berkaitan dengan masalah agama bagi penduduk bumi putera berujung dengan dibentuknya sebuah lembaga peradilan agama.77 Lembaga ini dinamakan dengan Pristerraad
78 berdasarkan Statsblaad 1882 Nomor 152 dan dibentuk di setiap wilayah Landraad atau Pengadilan Negeri.
Kondisi politik hukum adat mulai mengalami perubahan signifikan sejak kemunculan beragam kritikan terhadap regulasi yang sudah ada sebelumnya. Pada masa ini juga mulai diperkenalkan het
indische adat-recht.79 Snouck Hurgronje yang berkedudukan sebagai Penasehat Hindia Belanda mengkritik pola hubungan antara nilai-nilai
75 Supomo dan Djokosutono, Sejarah Politik Hukum Adat 1609-1848 (Jakarta;
Djambatan, 1955), 26. 76 Munawir Sadjali, “Landasan Pemikiran Politik Hukum Islam dalam rangka
manantukan Peradilan Agama di Indonesia”, dalam Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek, ed. Tjun Suryaman (Bandung: Remaja Rosda karya, 1991), 43-44
77 Kegagalan Belanda ini dikarenakan tidak efektifnya pemberlakuan Staatsblad 1853 Nomor 56 terkait penyerahan kewenangan kepada penghulu untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang berhubungan dengan perkawinan, kewarisan dan perkara perdata Islam lainnya. Keterangan lebih lanjut dapat disimak dalam Ratno Lukito, Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia (Jakarta: INIS, 1998), 30-33.
78 Priesterraad berarti Pengadilan Pendeta. Oleh beberapa ahli, penamaan ini dianggap keliru mengingat banyak perkara yang berkaitan dengan masyarakat yang menganut ajaran Islam. Hal ini tergambar dari wewenang diemban oleh institutsi ini yang meliputi perkara antara orang Islam dan diselesaikan berdasarkan hukum Islam.
79 Konsep adat recht (hukum adat) yang dimunculkan oleh Snouck Hurgronje, yang kemudian dielaborasi oleh Cornelis van Vollenhoeven, pada awalnya didefenisikan sebagai kebiasaan, cara, aturan, tata karma dan kesopanan. M.A. Jaspan, “In Quest of Law: The Perplexity of Legal Syncretism in Indonesia”, CSSH, Volume VIII, No. 3 (1965): 252.
RELASI ISLAM DAN ADAT DI MINANGKABAU | 45
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Islam dengan golongan bumi putera. Konsep ini dikenal dengan teori receptie yang menyatakan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat. Secara sederhana, berdasarkan teori ini maka pemberlakuan hukum Islam harus diresepsi atau diterima terlebih dahulu oleh hukum adat setempat.
Gagasan pokok dalam pemikiran Snouck Hurgronje pada awalnya didasarkan pada penekanan signifikansi Islam dalam kehidupan penganutnya dan cara yang dikembangkan dalam sebuah sistem budaya tertentu. Adat menjadi elemen penting dalam kehidupan muslim pada masa Hindia Belanda melebihi ajaran Islam. Kondisi ini sangat jauh berbeda dengan hipotesis yang disampaikan oleh Keijzer dan van den Berg.80 Penekanan Snouck Hurgronje terhadap hukum adat daripada hukum Islam tercipta melalui upaya memahami masyarakat Aceh dan tertuang dalam karyanya yang berjudul de Atjehters. Melalui karyanya ini, Snouck Hurgronje mengemukakan pandangan bahwa adat dan Islam merupakan dua domain yang berbeda dan terpisah, dalam ranah budaya, sosial dan politik. Bahkan, hubungan antara adat dan Islam memperlihatkan ketegangan dan konflik, seperti yang terlihat dalam pola hubungan sosial politik antara uleebalang dan ulama.81
Kewenangan seorang penasehat untuk ikut serta terhadap urusan keagamaan sudah dimulai sejak tahun 1859. Sebagai seorang kolonialis, Snouck Hurgronje berpendapat82 bahwa pemerintah Belanda membutuhkan inlandch politiek yang berbentuk kebijakan mengenai penduduk pribumi dalam usaha memahami dan menguasai pribumi. Politik ini didasari sebuah anggapan utama bahwa pada dasarnya musuh kolonialisme bukanlah Islam dalam dimensi agama, melainkan Islam dalam dimensi doktrin politik.83 Kemunculan teori receptie ini berawal
80 B.J. Boland dan I. Farjon, Islam in Indonesia: a Bibliographical Survey
1600-1942 With Post 1945 Addenda (Dordrcht: Foris Publications, 1983), 20. 81 Proyek kolonial terhadap Islam di Hindia Belanda didasarkan pada
keberadaan dua entitas yang diasumsikan terpisah dalam kehidupan seorang muslim. Snouck Hurgronje kemudian merekomendasikan kepada Pemerintah Kolonial untuk menggandeng kelompok uleebalang dengan cara memberikan penghargaan terhadap mereka agar mereka bersedia menerima kekuasaan Belanda. Jajat Burhanudin, Ulama &
Kekuasaan, 170-171. 82 Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda (Jakarta: LP3ES, 1986), cet-2,
10-11. 83 Harry J. Benda, The Crescent and The Rising Sun (tk: The hauge, 1958), 22-
23. Pada kenyataannya, Islam seringkali merepotkan Pemerintahan Hindia Belanda meskipun Islam di Indonesia masih terkesan dengan adanya distorsi kepercayaan Animisme dan Hindu. Hal ini dikarenakan orang Islam di Indonesia beranggapan bahwa agamanya merupakan alat pengikat yang kuat dan sebagai pembeda jati diri dengan
46 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
dari keinginan Snouck Hurgronje agar warga pribumi tidak memegang ajaran Islam dengan teguh. Hal ini dikarenakan setiap orang yang memegang teguh ajaran Islam dan menerapak hukum Islam tidak mudah dipengaruhi oleh peradaban Barat. Berdasarkan pertimbangan untuk melancarkan rencananya, Snouck Hurgronje berpendapat untuk menjalankan politik devide et empera (politik pecah belah).
Beragam usaha yang dilakukan oleh Hurgronje secara terus menerus dan sistematis berujung dengan diganti teori receptie in
complexu dengan teori receptie. Hal ini dapat dipahami dari bunyi pasal 34 ayat (2) Indische Staatsregeling (IS)84 yang menyatakan bahwa dalam hal penyelesaian perkara perdata antar sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim Islam, namun apabila keadaan tersebut harus telah diterima oleh hukum adat mereka dan tidak ditentukan lain oleh ordansi. Kondisi ini menggambarkan bahwa eksistensi yang diakui hanyalah hukum adat, sementara itu hukum Islam dianggap tidak ada. Hukum Islam akan mempunyai arti dan manfaat bagi para pemeluknya hanya apabila telah diresepsi oleh hukum adat setempat. Pandangan yang dikemukakan oleh Hurgronje ini kemudian dipertahankan dan diteruskan oleh Cornelis van Vollenhoeven dan Barend Ter Haar.85 Kedua tokoh ini dikenal sangat gigih dalam mempertahankan hukum adat bagi masyarakat pribumi dan kemudian mempertentangkannya dengan hukum Islam.
yang lainnya. Deliar Noer, The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942 (London: KI, 1973), 164.
84 Regulasi ini kemudian diiringi dengan ditetapkannya Staatsblaad 1937 Nomor 116 yang menyatakan bahwa Peradilan Agama di Jawa dan Madura hanya berwenang menangani perkara perkawinan saja, sementara perkara waris menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Pada tahun yang sama juga ditetapkan Staatsblaad Nomor 638 dan 639 tentang pendirian Kerapatan Qadhi dan Kerapatan Qadhi Besar untuk wilayah Kalimantan Selatan dengan kewenangan yang sama dengan Pengadilan Agama di jawa dan Madura. Hof voor Islamietische Zaken (Mahkamah Islam Tinggi) dibentuk berdasarkan Staatsblaad 1937 Nomor 610 sebagai lembaga peradilan tingkat banding dagi Pengadilan Agama.
85 Kedua tokoh ini dikenal sebagai pembela hukum adat. Meskipun demikian, pada dasarnya terdapat perbedaan dalam memandang kedudukan hukum adat. Cornelis Cornelis van Vollenhoeven memandang hukum adat sebagai sesuatu hal yang menjadi hak milik rakyat dan menyampaikan gagasannya dalam sebuah buku yang berjudul de Ontdekking van Het Adatrecht (Penemuan Hukum Adat). Sementara itu, Ter Haar memandang bahwa hukum adat merupakan bagian dari kebijakan penguasa dan menyampaikan idenya melalui tulisan yang berjudul Beginselen en Stelsel van Het
Adatrecht (Asas-asas dan Susunan Hukum Adat). Budi Kisworo, “Relevansi Pemikiran Hazairin tentang Hukum Islam terhadap Proses Pembentukan Hukum Nasional” (Desertasi SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2000), 52.
RELASI ISLAM DAN ADAT DI MINANGKABAU | 47
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Pergumulan hukum Islam dengan hukum adat di Indonesia terutama di wilayah Sumatera Barat selalu digambarkan sebagai dua hal yang bertentangan. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh pendekatan konflik yang mereka pakai dalam menyelesaikan masalah antara eksponen hukum adat dan hukum Islam. Kondisi ini tergambar jelas dari pernyataan van Vollenhoeven bahwa hukum adat harus dipertahankan sebagai hukum bagi golongan bumiputera dan tidak boleh didesak oleh kepentingan hukum barat.86 Hal ini dikarenakan apabila hukum adat didesak oleh hukum barat, maka hukum Islam akan berlaku, sementara kondisi ini tidak boleh terjadi di Hindia Belanda. Konflik antara hukum Islam dengan hukum adat pada dasarnya hanyalah isu yang diusung oleh para politikus hukum pada era kolonialisasi. Ter Haar87 menyatakan bahwa antara hukum adat dengan hukum Islam tidak mungkin bersatu apalagi bekerjasama. Kondisi ini dikarenakan perbedaan titik tolak di antara keduanya. Perbedaan titik tolak ini terkadang dapat diperlunak, namun seringkali tidak dapat diselesaikan. 2. Gerakan dan Perang Paderi
Akhir abad XVIII menandai sebuah titik balik dengan berakhirnya kontrol VOC dan mulainya pemerintahan langsung oleh Kerajaan Belanda. Dalam tahun-tahun berikutnya, hukum Islam secara bertahap dikebiri oleh otoritas penjajahan Belanda.88 Hubungan antara Islam dan masyarakat Minangkabau mengalami perubahan penting setelah muculnya gerakan Paderi di awal abad XIX.89 Term paderi90 pada abad XIX tidak dikenal di Minangkabau. Pada masa itu, ada dua kelompok yang saling bertentangan, yaitu golongan hitam dan golongan putih.
86 Mochtar Naim, Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau
(Padang: Centre of Minangkabau Studies, 1968), 171. 87 Barend Ter Haar, Hukum Adat dan Polemik Ilmiah (Jakarta: Bharatara,
1973), 29. Ter Haar menggambarkan pola hubungan antara hukum Islam dan hukum adat itu sebagai sebuah pertentangan antara hukum perdata adat dengan hukum perdata Islam dalam masalah perkawinan dan kewarisan. Pertentangan antara dua hal ini terlihat tidak akan terselesaikan. Deliar Noer, The Modernist Muslim Movement, 19.
88 Ratno Lukito, Islamic Law and Adat Encounter, 30. 89 Audrey Kahin, Dari Pemberontakan ke Integrasi, 7. 90 Terdapat perbedaan pendapat berkaitan dengan kemunculan term Paderi di
Minangkabau. Ada yang berpendapat bahwa kata Paderi berasal dari bahasa Portugis yaitu padre yang berarti bapak, merupakan sebutan yang ditujukan kepada pendeta. Pendapat lain menyatakan bahwa term Paderi berasal dari kada Pedir (Pidie) yang merupakan bandar di pesisir utara Aceh, tempat berkumpulnya pada ulama Minangkabau yang hendak berangkat ke Mekah. M. D. Mansoer, et. all., Sedjarah
Minangkabau, 117.
48 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Golongan putih inilah yang kemudian dikenal sebagai golongan paderi. Pertentangan yang terjadi antara golongan hitam dan golongan putih di Minangkabau pada masa awal abad XIX bukanlah konfrontasi vis a vis antara adat dengan agama. Golongan adat merupakan orang yang beragama, demikian juga halnya dengan golongan agama yang masih hidup dalam lingkungan adat. Sumber utama yang menjadi pertikaian pada awalnya hanyalah dalam masalah kebiasaan dalam keagamaan yang kemudian meruncing menjadi masalah politik. Pertikaian ini berawal dari perbedaan pendapat antara golongan Shatariyyah yang pada waktu itu telah lama dianut oleh masyarakat setempat dengan golongan Hanbali yang baru berkembang dalam masyarakat.
Ketidakserasian dalam pelaksanaan syariat di Minangkabau berubah menjadi pertikaian paham yang sangat sengit dalam bidang pemerintahan karena menyangkut kekuasaan prestise seorang penghulu beserta Dewan Nagari. Meskipun dalam masyarakat ada tokoh alim ulama, namun pada masa itu alim ulama hanya mempunyai wewenang dalam menyampaikan ajaran Islam dan pembinaan generasi muda dalam surau.91 Rakyat pada waktu itu lebih patuh kepada penghulu dari pada ulama. Berbekal semangat adanya golongan Wah}a>bi,92 kalangan ulama juga ingin agar suara mereka bisa didengar oleh masyarakat. Hal inilah yang kemudian berkembang di tengah-tengah masyarakat. Perebutan kekuasaan antara golongan penghulu dengan golongan ulama yang seringkali menimbulkan perbenturan dalam masyarakat dan meningkatnya intensitas bentrokan fisik antar sesama anggota masyarakat dalam nagari.
Gerakan pembaharuan Islam di Minangkabau muncul sejak dasawarsa awal abad XIX, yang kemudian mengalami radikalisasi, terutama ketika ketiga orang haji kembali dari Mekah.93 Islam di Indonesia memang menonjol karena keanekaragamannya. Sebagian besar penganut Islam di Indonesia pada dasarnya adalah kaum Sunni (ortodoks
91 Sistem pendidikan pada masa pra-paderi dan pra-kolonial di Minangkabau tidak sepenuhnya bersifat lokal dan dan berfokus pada surau-surau dan kampung-kampung. Dunia pendidikan Islam pada ini mulai bersifat inheren dan konsmopolitan. Kaum reformis mulai menusuk masuk ke dataran tinggi. Jeffrey Hardler, Sengketa Tiada
Putus, 33. 92 Kemunculan golongan Wahabi di Minangkabau merupakan efek domino dari
adanya perpecahan kekuasaan dan aliran politik dalam Islam. Pada pertengahan abad XVIII, Muh}ammad ibn Wah}ab, seorang pemimpin suku Badui menghidupkan kembali mazhab Hanbali di tengah-tengah sukunya. Pengikutnya dikenal dengan istilah kaum Wahabi dengan semangat pemurnian ajaran Islam yang pada saat itu sudah bercampur dengan bid’ah. M. D. Mansoer, et. all., Sedjarah Minangkabau, 119.
93 Azyumardi Azra, Surau, 5.
RELASI ISLAM DAN ADAT DI MINANGKABAU | 49
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
dan dibedakan dari kaum Shiah) dan merupakan penganut mazhab hukum Sha>fii. Banyak kalangan muslim Indonesia yang terlibat dengan mistik sufi, terutama tarekat Shatariyyah, Naqshabandiyah, Qadiriyyah dan gabungan antara Qadariyyah dan Naqshabandiyah. Akan tetapi, di balik keseragaman ini terlihat adanya perbedaan dan penyimpangan-penyimpangan dari ajaran Islam dan ketidaktahuan.94 Islam di Indonesia sangat dipengaruhi oleh eksistensi adat dan ide-ide lokal.
Terseret dalam gelombang reformisme Islam abad ke-XVIII, Tuanku nan Tuo mendesakkan pengamalan ajaran Islam agar lebih ketat dan meminta untuk mengakhiri perbudakan yang muncul bersamaan dengan peningkatan intensitas perdagangan. Adanya peningkatan perdagangan ini menaikkan tingkat kekayaan dalam masyarakat, sehingga tidak sedikit dari kalangan masyarakat yang mampu dan melaksanakan haji dan kembali ke Indonesia. Pada masa ini, Kaum Wahabi terlibat upaya penaklukkan dan keberhasilan menduduki Mekah pada tahun 1803 dan menguasainya dari tahun 1806 hingga tahun 1812.95 Kelompok Wahabi menolak penafsiran tekstual sebagai sebuah inovasi dan menuntut ketaatan dan mengikuti cara hidup yang dijelaskan dalam Alquran dan hadis.
Gerakan Wahabi sampai di Minangkabau dibawa oleh tiga tokoh Minangkabau yang berada di Mekah pada waktu terjadinya revolusi Wahabi ini.96 Tiga tokoh tersebut adalah Haji Sumanik dari Luhak Tanah Datar, Haji Piobang dari Luhak Limapuluh Kota dan Haji Miskin dari Luhak Agam. Pada tahun 1803, ketiga tokoh ini kembali ke Minangkabau dengan berbekal semangat pemurnian ajaran Islam.97 Kondisi politik Minangkabau pada saat itu sangat mendukung berkembanganya paham ini. Kelemahan ulama pada saat itu dalam memberlakukan pelarangan terhadap kebiasaan-kebiasaan seperti berjudi dan menyabung ayam
94 M. C. Ricklefs, A History of Modern Indonesia, 351-352. 95 Hamid Algar, Wahhabism: A Critical Essay (New York; Islamic Publications
International, 2002), 20. 96 Jeffrey Hardley, Sengketa Tiada Putus, 36. 97 Semangat ini merupakan awal dari kemunculan gerakan Wahabi itu sendiri.
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, salah satu alasan kemunculan semangat Wahabi yang digalang oleh Muh}ammad ibn Wah}ab adalah karena kebencian terhadap kaum Shiah. M. D. Mansoer, et. all., Sedjarah Minangkabau, 119. Sepulangnya ketiga tokoh tersebut dari Mekah, mereka menggunakan ajaran Wahabi itu sebagai model dalam mendirikan gerakan Paderi yang kemudian berkembang subur di Minangkabau. Cristine Dobbin, Islamic Revivalism, 128-131, Audrey Kahin, Dari Pemberontakan ke
Integrasi, 7. Lihat juga dalam Hamka, Ajahku: Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim
Amrullah dan Perdjuangan Kaum Agama di Sumatera (Jakarta: Djajamurni, 1967), cet-3, 26.
50 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
dimanfaatkan diambil alih oleh semangat Wahabi yang dikobarkan oleh ketiga tokoh tersebut. Semangat Wahabi ini juga menarik perhatian dari seorang penghulu muda dari Nagari Pandai Sikek Agam yang bernama Si Kuncir Datuk Batuah. Penganut paham Wahabi merasa bahwa mereka sudah seharusnya mengambil tindakan tegas. Usaha pembersihan mulai dilancarkan terhadap kebiasaan-kebiasaan yang dianggap bidah.98 Hal ini jelas saja menimbulkan pertikaian yang luar biasa dalam masyarakat. Pertikaian tersebut bersumberkan pada ideologi agama untuk tujuan perebutan politik dan kekuasaan.
Rakyat yang pada awalnya bebas bertindak dalam urusan sehari-hari merasa terkungkung dengan gerakan yang dilaksanakan oleh kelompok Wahabi ini. Rakyat yang terjepit kemudian meminta perlindungan kepada kaum penghulu adat. Penghulu adat yang merasa semakin terpojokkan dengan tindak tanduk golongan Wahabi kemudian menggalang kekuatan bersama rakyat yang menolak gerakan tersebut. Hal inilah yang kemudian menjadi dua titik kekuatan yang saling berseberangan di Minangkabau.
Perebutan kekuasaan dan kekuatan politik di Tanah Datar pada akhirnya diselesaikan secara perundingan yang diprakarsai oleh Tuanku Lintau. Upaya damai ternyata berakhir dengan pertikaian yang diakibatkan oleh ambisi salah seorang pengikut Tuanku Lintau yang ingin membunuh seluruh keluarga kerajaan.99 Kekacauan pun terjadi dalam perundingan itu karena terbunuhnya Anggota Dewan Nagari. Hal inilah yang kemudian menimbulkan ketakutan yang luar biasa di kalangan masyarakat, sehingga sebagian besar masyarakat tunduk dalam kekuasaan dan dominasi Wahabi. Peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa yang menumbangkan Kerajaan Minangkabau.
Berbeda dengan daerah darek, perkembangan pengaruh Wahabi di daerah rantau bagian utara, di Lembah Alahan Panjang (Lubuk Sikaping), tidak mendapatkan reaksi hebat. Perkembangan Wahabi di daerah ini pada awalnya bersifat defensif, namun kemudian berubah menjadi ofensif. Ditambah lagi dengan kedudukan daerah rantau yang jauh dari
98 Gerakan Wahabi seperti pergerakan Paderi merupakan pergerakan yang
bersifat militan dan puritan. Wahabi ingin membersihkan agama Islam Arab dari khurafat yang menggerogoti ajaran Islam sejak kematian Rasulullah S.A.W. dan menolak atau tidak menolerir cara-cara mereka beriman dengan pengamalan yang salah. Elizabeth E. Graves, Asal-Usul Elite Minangkabau, 49.
99 Pada dasarnya, kaum paderi yang berada di Luhak Tanah Datar hidup secara sederhana. Namun, di antara pengikut Tuanku Lintau, ada seorang pengikut yang sangat ambisius untuk menguasai kerajaan, namanya adalah Tuanku Lelo. M. D. Mansoer, Sedjarah Minangkabau, 124.
RELASI ISLAM DAN ADAT DI MINANGKABAU | 51
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
daerah darek, sehingga kekuatan mengikat akan ketentuan adat lebih longgar dibandingkan daerah darek. Setelah merasa mempunyai kekuatan yang dihimpun di Lembah Alahan Panjang, kelompok Wahabi ini kemudian memulai melanjutkan dominasinya ke daerah-daerah sekitar sampai ke Tapanuli Selatan pada tahun 1816-1833.
Konflik keagamaan di Minangkabau antara Shatariyyah dan mazhab Hanbali berakhir dengan kemenangan golongan ketiga, yaitu mazhab Sha>fii. Demikian pula halnya dengan konflik yang terjadi antara kelompok Paderi dengan kelompok adat yang dimenangkan oleh pihak ketiga, yaitu Belanda.100 Kemenangan mazhab Sha>fii di Minangkabau didasari oleh kemenangan Turki Utsmani yang menganut mazhab Sha>fii meruntuhkan kekuatan Wahabi di tanah Arab. Mazhab Sha>fii kemudian berkembang pesat dan mempunyai pengaruh kuat di Arab. Hal ini dikarenakan mazhab Sha>fii lebih toleran dibandingkan mazhab Hanbali dan lebih bisa diterima logika apabila dibandingkan dengan aliran Shatariyah yang sarat akan mistik.
Suasana perpolitikan di Minangkabau pada tahun 1819 sangat berbeda. Pada saat itu, Inggris mengembalikan Kota Padang kepada Belanda. Pada tahun 1824, daerah darek Minangkabau juga sudah dikuasai oleh Belanda. Ulama Minangkabau yang pulang beribadah haji dan hendak kembali ke kampungnya pasca tahun 1824 dibantu oleh Belanda dalam pengembangan mazhab Sha>fii. Hal ini bertujuan untuk semakin melemahkan pengaruh Wahabi di Minangkabau. Terdesak oleh kekuatan Belanda di daerah darek, kelompok Wahabi kemudian mundur dan bertahan di Bonjol. Karena tidak mempunyai kekuatan yang berarti, akhirnya pusat pertahanan kaum Paderi berhasil dikalahkan dan Belanda akhirnya menguasai Bonjol. Melihat konflik yang terjadi antara kaum adat dengan kaum Paderi di Minangkabau, Belanda memanfaatkan kesempatan ini untuk semakin melemahkan kekuatan Wahabi di Minangkabau.
Pada dasarnya, Alam Minangkabau melalui kekuatan Paderi yang pada saat itu berada di pesisir barat Sumatera merupakan suatu kekuatan politik yang sangat mengancam keberadaan Belanda. Kelompok Paderi mempunyai hubungan langsung dengan Inggris melalui Tiku, Air Bangis dan Pariaman. Kondisi semakin mengancam Belanda mengingat adanya ketegangan politik antara Belanda dan Inggris di Asia Tenggara. Usaha perluasan penjajahan Belanda ke Minangkabau mempunyai dua tujuan utama. Pertama adalah usaha untuk melemahkan posisi ekonomi Inggris di wilayah pesisir timur pulau Sumatera. Tujuan kedua adalah usaha
100 M. D. Mansoer, et. all., Sedjarah Minangkabau, 126.
52 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
menghentikan pergerakan dan perembesan pengaruh ideologi kaum Paderi ke wilayah pedalaman Minangkabau.
Usaha penguasaan konsesus ekonomi dan politik Belanda dijalankan dengan politik mendekati golongan lemah dan terjepit di daerah yang sedang mengalami pertentangan-pertentangan politik yang hebat. Sementara itu, pasca penyerahan kekuasaan dari Inggris ke Belanda pada tahun 1819, kekuatan kelompok Paderi di Minangkabau semakin mengakar. Meskipun kelompok Paderi mempunyai supremasi militer yang kuat, namun ia tidak mempunyai sebuah kekuasaan riil dengan sistem pemerintahan terpusat. Meskipun kaum Paderi tidak berhasil memperoleh kekuasaan secara riil dalam bidang pemerintahan sebagaimana layaknya kerajaan Minangkabau sebelumnya, namun kaum adat mengakui dominasi yang dimiliki oleh kaum Paderi pada masa ini.101 Kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh Belanda untuk melakukan konfrontasi dengan kaum Paderi. Kaum adat yang semakin lemah dan terjepit oleh dominasi politik kaum Paderi dimanfaatkan oleh Belanda untuk semakin melemahkan kekuatan Inggris. Hal ini juga ditunjang karena eratnya hubungan dagang antara kaum Paderi di pesisir dengan Inggris.
Penghulu yang semakin terjepit oleh kelompok Paderi kemudian melarikan diri ke benteng-benteng pertahanan Belanda dan meminta bantuan. Belanda menyanggupi permintaan yang diajukan oleh penghulu tersebut dengan syarat adanya penyerahan kekuasaan akan wilayah-wilayah Minangkabau kepada Belanda. Usaha negosiasi dan perjanjian yang dilakukan antara kelompok adat dengan Belanda ini terjadi pada tahun 1821.102 Setelah perjanjian ini, Belanda kemudian mulai menempatkan kekuatan militer beserta persenjataan mereka pada beberapa wilayah di pedalaman Minangkabau.
Kekuatan persenjataan dan dominasi keunggulan Belanda dalam berbagai hal, memaksa perjanjian tersebut dilaksanakan berdasarkan hukum barat, bukan berdasarkan hukum adat. Perjanjian tersebut dilakukan secara tertulis. Sehingga, pada waktu itu Belanda mempunyai kekuatan tertulis sebagai bukti kekuatan kedudukannya dalam mengawasi
101 M.D. Mansoer, dkk, Sedjarah Minangkabau, 130. 102 Du Pay mengadakan perundingan dengan keluarga Kerajaan Pagaruyung
yang diwakili oleh Sultan Alam Bagagar Syah yang merupakan kemenakan Raja Alam yang terakhir di Pagaruyung dan para penghulu yang anti terhadap pergerakan kaum paderi. Berdasarkan perjanjian tersebut, kedua belah pihak setuju untuk menandatangani perjanjian kerjasama pada 10 Februari 1821. Isi perjanjian tersebut menyatakan bahwa untuk melindungi keluarga kerajaan dan penduduk, Belanda akan menempatkan pasukannya di tempat-tempat strategis. Amir Sjarifoedin, Minangkabau, 446-447.
RELASI ISLAM DAN ADAT DI MINANGKABAU | 53
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
lalu lintas perdagangan pada beberapa wilayah strategis di Minangkabau. Tidak terbatas hanya sampai di situ, berdasarkan perjanjian tersebut pula rakyat diberatkan dengan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan logistik Belanda selama di Minangkabau. Hal inilah yang kemudian semakin memperuncing perselisihan pada kalangan masyarakat di Minangkabau. Hal ini juga yang menjadi titik awal terjadinya Perang Sumatera (1821-1904), meskipun untuk regional Minangkabau peperangan ini berakhir pada tahun 1845.
Kaum Paderi memproklamirkan peperangan menentang kolonialisme Belanda sebagai perang sabil pada tahun 1825. Hal ini menimbulkan reintegrasi antara kaum Paderi dengan kaum adat dengan tujuan membatasi gerak Belanda di beberapa wilayah Minangkabau. Pecahnya Perang Diponegoro di Jawa pada tahun 1825-1830 tidak dimanfaatkan dengan baik oleh masyrakat Minangkabau untuk menghapus dominasi Belanda, sehingga setelah peperangan tersebut, Belanda kembali memusatkan kekuatan militernya di Minangkabau hingga berhasil menguasai Minangkabau pada tahun 1832.
Tingginya intensitas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Belanda di Minangkabau memicu adanya Pertemuan Tandikat pada tahun 1832.103 Hal ini mendorong adanya kebulatan tekad bagi masyarakat Minangkabau untuk melakukan upaya pengusiran Belanda sehingga Perang Minangkabau kembali berkobar. Kegagalan Belanda dalam bidang militer memaksanya untuk menempuh jalur diplomasi guna mengulur waktu untuk kembali menghimpun kekuatan. Hal inilah yang mendorong adanya Plakat Panjang yang diumumkan Belanda pada Oktober 1833 dan berhasil memecah konsentrasi kekuatan masyarakat Minangkabau. Setelah merasa mempunyai kekuatan yang cukup, Belanda melanggar Plakat Panjang dan menyerang Bonjol yang merupakan pusat kekuatan Minangkabau pada 1834-1837. Penyerangan ini berhasil melumpuhkan kekuatan Minangkabau. Hal ini ditandai dengan ditawannya Tuanku Imam Bonjol pada tahun 1837.
Kekalahan masyarakat Minangkabau dalam Perang Paderi yang ditandai dengan semakin kuatnya dominasi politik dan ekonomi Belanda pada dasarnya tidaklah menyelesaikan pertikaian agama dalam
103 Perjanjian ini dipicu oleh semakin meningkatnya rasa kemarahan dan
kebencian kaum adat terhadap Belanda sehingga kaum adat melakukan perlawanan. Untuk melaksanakan niatnya, kaum adat harus mengadakan kerjasama dengan kaum paderi. Keinginan ini disambut baik oleh kaum paderi dan terbukti dengan adanya perjanjian Tandikat yang dilaksanakan pada akhir tahun 1832. Dalam perjanjian ini, Imam Bonjol ditunjuk sebagai pimpinan perlawanan masyarakat Minangkabau terhadap Belanda. Amir Sjarifoedin, Minangkabau, 451.
54 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
masyarakat Minangkabau. Guna memantapkan dominasinya di Minangkabau, Belanda membantu perkembangan mazhab Sha>fii di Minangkabau. Hal ini terlihat dalam beberapa fasilitas yang diberikan oleh Belanda kepada Ulama Sha>fii dalam mengembangkan ajarannya. Semakin kuatnya dominasi Belanda dalam monopoli jalur perdagangan di pesisir timur pantai Sumatera merupakan salah satu alasan pemicu meletusnya Perang Aceh yang merupakan bagian dari rangkaian Perang Sumatera.
Belanda memanfaatkan tatanan tradisional masyarakat Minangkabau untuk memudahkan pemerintahannya dengan melakukan beberapa modifikasi terhadap lembaga-lembaga pemerintahan tradisional Minangkabau. Kerapatan Nagari dijadikan sebagai lembaga pemerintahan terendah. Pada awalnya para penghulu di Minangkabau memimpin secara bersama-sama, namun sejak dijadikannya Kerapatan Nagari sebagai suatu sistem pemerintahan terendah, maka para penghulu diharuskan memilih salah satu di antara mereka yang akan menjadi kepala nagari (nagarihoofd). Cara seperti inilah yang dilakukan oleh Belanda untuk memperkenalkan sistem pemerintahan yang otoriter kepada masyarakat Minangkabau. Belanda juga mengubah pola federasi nagari-nagari (lareh), yang pada awalnya merupakan aliansi longgar beberapa nagari yang didasarkan atas prinsip saling menguntungkan yang kemudian berubah menjadi lembaga pemerintahan di tingkat kecamatan yang dipimpin oleh seorang penghulu yang dipilih dari para penghulu yang ada di daerah tersebut.104 Dengan demikian, terbentuklah sebuah tatanan pemerintahan yang baru di Minangkabau, di mana nagari bukanlah sebuah titik pemerintahan tertinggi lagi.
Penggunaan tatanan tradisional masyarakat Minangkabau sebagai tatanan administratif pemerintahan kolonial tidaklah memudahkan Belanda untuk menjalankan kekuasaannya dan menguras sumber daya alam Minangkabau. Pada tahun 1914, ditetapkanlah Ordansi Nagari. Aturan ini dimaksudkan untuk menegakkan kembali komunitas nagari yang otonom, namun tujuan sebenarnya adalah untuk membatasi keanggotaan Kerapatan Nagari bagi para penghulu inti yang diakui oleh
104 Nagarihoofd merupakan istilah yang diberikan kepada orang yang
berkedudukan sebagai penghulu kepala. Larashoofd merupakan istilah yang diberikan kepada Tuanku Lareh di Minangkabau pada masa itu. Istilah tersebut dipergunakan oleh Elizabeth E. Graves untuk menggambarkan perbedaan sistem tradisional Minangkabau dengan sistem yang diciptakan oleh Belanda. Penejelasan lebih lanjut lihat Elizabeth E. Graves, Asal-Usul Elite Minangkabau, 82. Lihat juga Audrey Kahin, Dari
Pemberontakan ke Integrasi, 10.
RELASI ISLAM DAN ADAT DI MINANGKABAU | 55
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Belanda.105 Dengan keberadaan hak dan kewenangannya untuk memilih penghulu ini, Belanda pada dasarnya mengangkangi hak-hak prerogatif adat dan membedakan antara kelompok adat yang diakui dan tidak diakui oleh pemerintah Belanda.106 Keadaan ini semakin mengikis nilai-nilai tradisional Minangkabau, karena dengan berlaku sistem pemerintahan ini, penghulu suku kehilangan fungsi aslinya dalam pemerintahan.
Gelombang pembaharuan dalam bidang pendidikan Islam di Minangkabau menimbulkan beragam ketegangan dalam masyarakat dengan menonjolkan ulama selaku tenaga pendidik modern Minangkabau. Kemunculan gelombang pembaharuan ini tidak bisa dilepaskan dari peranan Shekh Ah}ma>d Kha>tib al Minangkabawi.107 Salah satu murid beliau yang terkenal adalah Muhammad Yahya atau yang dikenal juga dengan Tuanku Simabur yang berasal dari Luhak Tanah Datar. Tuanku Simabur menyampaikan kecamannya terhadap ulama-ulama yang mendukung pelaksanaan praktek ilmu kewarisan adat Minangkabau yang berbeda dengan ketentuan Islam. Demikian juga halnya dengan beberapa praktek keagamaan lainnya. Pengaruh beliau sangat luas, bahkan sampai ke daerah-daerah pelosok Minangkabau. Melihat kegoncangan seperti ini, akhirnya Belanda turun tangan
105 Menurut Ordansi Nagari 1914, Kepala Nagari harus dipilih oleh dan dari kalangan penghulu inti yang posisi adatnya diakui oleh pemerintah. Penghulu-penghulu yang lain tidak diizinkan ikut serta dalam pemilihan. Taufik Abdullah, Schools and
Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatera 1927-1933 (Ithaca: Cornell Modern Indonesian Project, 1972), 23.
106 Audrey Kahin, Dari Pemberontakan ke Integrasi, 10-11. 107 Shekh Ah}mad Kha>tib al Minangkabawi adalah turunan dari seorang hakim
dari golongan paderi. Beliau adalah pemuda keturunan Minangkabau yang sudah menetap di Mekah pada pertengahan abad XIX. Beliau dididik dalam aliran tariqat
naqsha>bandi> di daerah asalnya. Namun setelah memperdalam hukum Islam di Mekah, beliau berbalik menjadi pengecam yang menentang tariqat itu sendiri. Beliau mendapat kehormatan untuk mengajar fiqih pada salah satu serambi di Masjid al H}ara>m di sekitar Ka’bah. Beliau juga merupakan tempat menumpang bagi para ulama dari Minangkabau yang hendak mendalami ilmu agama Islam di Mekah. Hal inilah yang mendorong masuknya pengaruh beliau sampai ke Minangkabau melalui ulama-ulama yang pernah menjadi murid beliau. Shekh Ah}mad Kha>tib al Minangkabawi bukanlah tokoh pertama yang memperkenalkan pembaharuan Islam di Minangkabau. Menurut Haji Agus Salim dalam seminarnya di Cornell University pada 4 Maret 1953, Shekh Ah}mad Kha>tib al
Minangkabawi tidak mempunyai hubungan yang cukup baik dengan Snouck Hurgronje ketika dia berada di Mekah pada tahun 1885. Lebih lanjut lagi, Haji Agus Salim menyatakan bahwa Shekh Ah}mad Kha>tib al Minangkabawi adalah seseorang yang sangat anti Belanda. Keterangan lebih lanjut dapat ditemukan dalam Hamka, Ajahku, 28-38, M. D. Mansoer, et. all., Sedjarah Minangkabau, 165-166, M. C. Ricklefs, A History
of Modern Indonesia, 353-355 dan Deliar Noer, The Modernist Muslim Movements, 38-40.
56 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
menangkap dan mengasingkan Tuanku Simabur ke Cianjur pada tahun 1904 dengan alasan telah mengganggu dan membahayakan ketertiban umum.
Usaha Belanda mengasingkan Tuanku Simabur ke Cianjur tidaklah mematikan pengaruhnya di Minangkabau. Bibit yang disemaikan oleh Tuanku Simabur kemudian dikembangkan oleh murid-murid beliau yang menjadi pelopor gerakan modernisme Islam pada abad XX. Para murid beliau yang terkenal di antaranya adalah Shekh Muhammad Djamil Djambek (Inyiak Djambek), Shekh Abdul Karim Amrullah (Inyiak Rasul), Shekh Abdullah Ahmad dan Shekh Khatib Ali. Sistem pendidikan yang dikembangkan oleh Inyiak Djambek dan Inyiak Rasul adalah sistem pendidikan pesantren yang dikembangkan pada beberapa daerah di Minangkabau. Konsep pendidikannya adalah mengajarkan paham modernisme Islam yang telah meninggalkan metode surau tradisional. Para murid dari pesantren ini tidak hanya berasal dari daerah Minangkabau saja, akan tetapi juga dari luar Sumatera dan bahkan juga ada dari Semenanjung Malaka.
Berbeda dengan metode yang diterapkan oleh Inyiak Djambek dan Inyiak Rasul yang mengadakan pembaharuan dalam pendidikan Islam dengan tidak struktur tradisional, dengan tetap menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar, Shekh Abdullah Ahmad mendirikan HIS met de Quran (Adabiah School)108 di Padang. Di lembaga ini, beliau memberikan pendidikan barat dengan berlandaskan Alquran. Dengan ini beliau menciptakan kaum intelektual barat yang mempunyai pengetahuan tentang Islam. Tujuan pendirian lembaga pendidikan ini adalah untuk mempersiapkan generasi muda yang mempunyai pengetahuan barat dengan tidak meninggalkan nilai-nilai pendidikan Islam. Usaha ini mendapat kecaman dan bahkan beliau penah dianggap telah menyebrang109 oleh Inyiak Rasul.
108 HIS met de Quran merupakan sebuah lembaga pendidikan setingkat Sekolah
Dasar (SD) pada waktu itu. HIS met de Quran yang didirikan oleh Shekh Abdullah Ahmad mendapat respon baik dari para saudagar Padang. Hal ini dikarenakan kebanyakan dari anak-anak mereka tidak diterima di HIS Gupernemen merupakan SD resmi yang dibangun oleh Belanda. Lembaga pendidikan ini pada akhirnya mendapat sokongan dan dukungan subsidi dari Pemerintah Kolonial Belanda. M. D. Mansoer, et. all., Sedjarah Minangkabau, 168.
109 M. D. Mansoer, et. all., Sedjarah Minangkabau, 168. Term ini pada dasarnya merupakan ungkapan atau idiom yang familiar di kalangan masyarakat tradisional Minangkabau. Maksud penggunaan term tersebut adalah untuk menggambarkan pertentangan pendapat dalam suatu kelompok yang pada awalnya berasal dari satu induk. Hal inilah yang terjadi antara Inyiak Rasul dengan Shekh Abdullah Ahmad. Kedua tokoh ini pada dasarnya sama-sama murid dari Tuanku
RELASI ISLAM DAN ADAT DI MINANGKABAU | 57
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Shekh Abdul Karim Amrullah dan Shekh Abdullah Ahmad pada waktu mengadakan kunjungan ke Mesir, mendapat penganugerahan gelar Doktor dari Universitas al Azhar di Kairo. Di samping berkedudukan sebagai ulama, beliau juga berprofesi sebagai jurnalis dengan karya-karya yang terkenal tegas dan kritis dalam mengecam berbagai tindakan Pemerintah Kolonial Belanda pada masa itu. Situasi ini sangat merugikan Belanda, hingga pada akhirnya beliau ditangkap dan dibuang ke Cianjur dengan alasan membahayakan ketenteraman umum di Minangkabau.
Kegelisahan di kalangan masyarakat Minangkabau semakin menjadi ketika munculnya satu golongan masyarakat baru sebagai akibat dari perubahan sistem ekonomi pada waktu itu.110 Golongan masyarakat baru ini terbebas dari ikatan tanah serta menjauhkan diri dari pengaruh adat dan agama.111 Kaum intelektual barat yang disokong oleh Belanda dalam upaya pemantapan dominasi ekonomi dan sosial politiknya berkembang menjadi ujung tombak masyarakat yang pada akhirnya berhasil menumbangkan kekuatan Belanda di Minangkabau.
3. Pendudukan Jepang
Jepang menguasai Indonesia dalam waktu yang relatif singkat. Jawa berhasil dikuasai dalam waktu satu minggu pada tanggal 8 Maret 1942. Dalam arti yang sebenarnya, Pemerintahan Belanda dengan semua bentuk kehebatan soliditasnya, secara praktis dan efisien hancur dalam sekejap.112 Pergeseran otoritas jajahan membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Perbedaan yang fundamental antara imperialisme Jepang dan Barat terletak pada karakter militernya. Pemerintah militer Jepang yang menguasai Indonesia pada gilirannya memegang semua urusan pemerintahan kolonial.113 Perubahan ini
Simabur. Namun mereka dengan pola pikir masing-masing mencoba mengembangkan paham pendidikan modern dengan metode yang berbeda.
110 Perubahan sistem ekonomi yang dimaksud adalah adanya peralihan dari sistem naturalwirtschaft ke sistem geldwirtschaft. M. D. Mansoer, et. all., Sedjarah
Minangkabau, 171. 111 Kelompok masyarakat baru ini merupakan para pelaku ekonomi dan
pengusaha kelas atas. Kelompok ini terbentuk karena semakin tingginya intensitas perekonomian di Minangkabau pada waktu itu. Kelompok ini bukanlah masyarakat tradisional (gameinschaft). Kelompok ini hanya mempunyai ekonomi di Minangkabau, sehingga tidak begitu terpengaruh dengan keberadaan adat dan Islam yang sangat dihormati oleh masyarakat sekitarnya.
112 Anthony Reid, The Indonesian National Revolution 1945-1950 (Connecticut; Greenwood Press, 1974), 10. Sebagaimana yang dikutip dalam Ratno Lukito, Islamic Law and Adat Ecounter, 50.
113 Ratno Lukito, Islamic Law and Adat Encounter, 50-51.
58 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
tentunya juga membawa pengaruh bagi sejarah panjang integrasi Islam dan adat Minangkabau di Sumatera Barat.
Layaknya Belanda pada masa awal kolonialisme, Jepang juga mempertahankan kebijakan Belanda dalam upaya menghormati kearifan lokal yang ada di Indonesia. Hal ini dituangkan dalam kebijakan bahwa adat istiadat lokal, praktek-praktek kebiasaan dan agama tidak boleh dicampurtangani untuk sementara waktu.114 Kolonialisme Jepang di Minangkabau dilakukan melalui politik ekonomi.115 Politik ini diawali dengan menyebarkan mata uang Jepang di kalangan masyarakat sehingga nilai tukarnya menurun. Sementara itu, berbagai barang kebutuhan sehari-hari diangkut dari gudang-gudang Belanda.
Kelangkaan barang kebutuhan keseharian ini berakibat pada semakin terjepitnya perekonomian rakyat. Hal ini didukung juga oleh susahnya sarana transportasi pasca terjadinya perang dunia. Kondisi meningkatnya inflasi ini terjadi hampir selama pendudukan Jepang, terutama pada tahun 1943. Pada tahun 1945, mata uang yang disebarkan bernilai 2,5% dari nilai nominalnya. Pengaturan pangan dan tenaga kerja secara paksa, gangguan transportasi dan gangguan umum telah mengakibatkan timbulnya kelaparan. Hal ini berdampak pada meningkatnya angka kematian dan semakin menurunnya angka kesuburan. Kondisi kehidupan sosial dan kesehatan masyarakat Minangkabau pada waktu itu sangat memperihatinkan. Usaha Jepang dalam menguasai Minangkabau tidak sebatas sampai di situ saja. Pasca terlepas dari penjajahan Belanda, Jepang berusaha untuk merubah kondisi sosial masyarakat Minangkabau. Hal ini terlihat dari beberapa kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Jepang.116
114 “Pokok-pokok Aturan Administrasi Militer pada Daerah Pendudukan”, 14
Maret 1942, Dokumen Menteri Angkatan Laut Jepang, dalam Harry J. Benda, et. all., Japanese Military Administrasion in Indonesia: Selected Documents (New Haven: Yale University Southeast Asia Studies, 1965, 29. Sebagaimana yang dimuat dalam Ratno Lukito, Islamic Law and Adat Encounter, 51.
115 Tujuan utama Jepang menguasai Indonesia adalah menyusun dan mengarahkan kembali perekonomian Indonesia dalam rangka menopang upaya perang Jepang dan rencana-rencana mendominasi ekonomi jangka panjang terhadap Asia Timur dan Asia Tenggara. M. C. Ricklefs, A History of Modern Indonesia, 408.
116Beberapa kebijakan yang dimaksud seperti kebijakan tentang keharusan mempelajari bahasa Jepang dan pelarangan penggunaan bahasa Belanda. Penanggalan pun dirubah dari penganggalan Masehi menjadi penanggalan Sumatera yang disamakan dengan waktu Tokyo dengan selisih 660 Tahun. M. D. Mansoer, et. all., Sedjarah
Minangkabau, 211.
RELASI ISLAM DAN ADAT DI MINANGKABAU | 59
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Masa pendudukan Jepang merupakan salah satu periode yang menentukan dalam perkembangan sejarah Indonesia.117 Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikasi yang terjadi pada masa itu. Bahasa Indonesia mendapat kesempatan untuk berkembang luas karena menjadi bahasa resmi di kantor-kantor pemerintahan, sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah menggantikan bahasa Belanda yang sebelumnya dipakai.118 Hal ini dinilai sangat penting dalam mempersatukan identitas bangsa pada era perjuangan pada masa itu.
Indikasi ini pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, dari sisi internal rakyat Indonesia sendiri. Ada beberapa faktor utama yang mendorong timbulnya usaha yang menentukan ini, di antaranya adalah munculnya semangat juang generasi muda di Minangkabau. Generasi muda di Minangkabau sebagai generasi penerus terbebas dari ikatan-ikatan pribadi dan pengalaman dengan Belanda sehingga mampu bersikap lebih objektif. Rasa cinta tanah air dan munculnya nilai nasionalisme yang tidak didorong oleh rasa sentimental semata kian berkembang dan meluas akibat tekanan batin yang Jepang.119 Kedua, dari sisi eksternal masyarakat adalah kekalahan Jepang dalam perang. Apabila seandainya tujuan Jepang untuk membentuk Kawasan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya tercapai, maka hanya ada sedikit harapan bagi kemerdekaan Indonesia sesungguhnya.
Pemerintahan Jepang, paling tidak secara teoritis, berusaha membuat simbol pemisahan total dengan Belanda. Semua simbol yang menunjukkan eksistensi Belanda harus dihapuskan. Demikian juga halnya dengan seluruh organisasi yang aktif pada masa Belanda dilarang.120 Pada bulan Agustus 1942, pulau Jawa masih berada dalam struktur pemerintahan sementara, namun kemudian dilantik suatu sistem pemerintahan yang dikepalai oleh seorang Gubernur Militer (gunseikan). Banyak orang Indonesia yang dilibatkan dan diangkat untuk mengisi
117 Sebelum ada serbuan Jepang, tidak ada satu pihak pun yang berusaha
melawan kekuasaan Belanda dengan serius. Pada waktu Jepang menyerah kepada tentara sekutu, telah berlangsung begitu banyak perubahan luar biasa yang memungkinkan terjadinya revolusi Indonesia. M. C. Ricklefs, A History of Modern Indonesia, 405.
118 Pada masa revolusi fisik, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa perjuangan merupakan salah satu ideologi pemersatu antar sesama suku bangsa di Indonesia. M. D. Mansoer, et. all., Sedjarah Minangkabau, 213.
119 Kemunculan semangat juang generasi muda ini didorong oleh adanya pelatihan militer yang diberikan Jepang kepada pemuda, mereka diajarkan disiplin dan menggunakan senjata modern. M. D. Mansoer, et. all., Sedjarah Minangkabau, 213.
120 Anthony Reid, The Indonesian National Revolution, 11. Lihat juga dalam dalam Ratno Lukito, Islamic Law and Adat Encounter, 51.
60 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
posisi pejabat-pejabat Belanda yang ditawan.121 Untuk semakin memudahkan usahanya menguasai Indonesia, Jepang menempuh upaya politik sosial122 guna mendorong mobilisasi rakyat besar-besaran. Rezim kolonial Jepang menampilkan semangat kemauan politis yang menjanjikan. Hal ini terindikasi dari prospek yang diberikan bagi kekuatan Islam dalam pemerintahannya.123
Setelah dibentuknya Kantor Urusan Agama di Jawa, Jepang memulai tatanan baru gerakan politiknya dengan mulai menciptakan beberapa organisasi politik.124 Tujuan didirikannya organisasi politik hanyalah untuk menjembatani pemerintahan Jepang dengan rakyat pribumi. Salah satu media yang paling memberikan peluang itu adalah dengan menyokong gerakan anti Belanda. Usaha ini berjalan mulus di daerah-daerah pelosok, namun tidak dengan tokoh-tokoh Islam perkotaan. Oleh sebab itu, Jepang mulai melirik tokoh-tokoh nasional untuk mempertahankan dominasinya di Indonesia. Oleh sebab Jepang baru memberikan perhatian lebih kepada kepulangan Soekarno, Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir. Atas permintaan Angkatan Darat ke-16, Soekarno bergabung dengan Mohammad Hatta dan Sjahrir. Soekarno tidak begitu tertarik dengan perbedaan-perbedaan teoritis antara fasisme dan demokrasi. Soekarno bergabung dengan Mohammad Hatta dalam
121 Dalam tatanan praksis, Pemerintah Jepang tidak dapat begitu saja membuang para pegawai dan ahli teknik Belanda. Pemerintah Jepang berpegang pada fakta bahwa dengan pemberhentian para pegawai Belanda maka akan terjadi kekurangan para ahli dari Indonesia untuk menjadi hakim pada pengadilan-pengadilan dan kantor-kantor jaksa. Ratno Lukito, Islamic Law and Adat Encounter, 53.
122 Upaya politik yang ditempuh Jepang terlihat dengan kebijaksanaan menghapuskan semua organisasi politik yang sudah ada sebelumnya. Pada Maret 1942, semua kegiatan perkumpulan politik dilarang dan resmi dibubarkan. Setelah pembubaran tersebut, kemudian Jepang mulai menata sistem perpolitikan baru. Pada masa ini, kalangan Islam menawarkan suatu jalan mobilisasi bagi Jepang dengan mendirikan Kantor Urusan Agama (shumubu) di Jawa. M. C. Ricklefs, A History of Modern
Indonesia, 411. Lihat juga dalam Ratno Lukito, Islamic Law and Adat Encounter, 54. 123 Baik dalam term institusional ataupun politis, adanya kebijakan penghentian
jabatan uleebalang di Aceh, yang dahulunya merupakan kekuatan dominan dalam administrasi lokal, memberikan harapan bagi bentuk pengakuan kepada hukum Islam seiring dengan diperolehnya kekuatan kontrol oleh orang Islam dalam praktek peradilan. Ratno Lukito, Islamic Law and Adat Encounter, 53.
124 Salah satu bentuknya adalah pendirian Gerakan Tiga A di Jawa. Di dalam organisasi ini terdapat satu subseksi Islam yang dinamakan dengan Persiapan Persatuan Umat Islam di bawah pimpinan Abikoesno Tjokrosoejoso (saudara sekaligus pengganti Tjokroaminoto sebagai Ketua PSII). Kegagalan dalam mendekati Kiyai perkotaan dalam melancarkan urusannya, kemudian Jepang mengalihkan perhatiannya kepada tokoh-tokoh nasional, seperti Soekarno, Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir. M. C. Ricklefs, A
History of Modern Indonesia, 412-414.
RELASI ISLAM DAN ADAT DI MINANGKABAU | 61
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
kerjasama meraih kemerdekaan dengan memberikan desakan-desakan kepada Jepang untuk segera memberikan kemerdekaan Indonesia.
Pada pertengahan tahun 1943, Jepang semakin menindas rakyat pribumi. Hal ini terlihat dari beberapa peraturan yang dikeluarkan seperti halnya larangan jarak tertentu melaut bagi para nelayan. Setiap wilayah dibagi-bagi dan ditunjuk seorang pemimpin yang bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi di wilayahnya. Setiap pemimpin tersebut mendapatkan latihan militer di Batusangkar. Apabila ada oknum yang tidak mau bergabung dalam pelatihan militer akan dianggap sebagai mata-mata sekutu. Setiap wanita yang sudah menikah ditugaskan untuk mengawasi gerak-gerik suaminya. Bahkan juga dibentuk satu kesatuan yang bertugas membantu polisi dalam mengawasi kaum petani hingga ke pelosok-pelosok daerah di Minangkabau. Setiap daerah diharuskan menyerahkan tenaga pemuda secara sukarela dalam kerja paksa yang diprakarsai oleh Jepang.
Untuk mempermudah pengaruh politiknya di Minangkabau, Jepang merangkul kalangan ulama125 yang tetap konsisten menyuarakan anti Belanda. Ulama dari semua kalangan diberikan fasilitas untuk memudahkan ruang geraknya. Bahkan Jepang juga memprakarsai terjadinya Muktamar Islam Asia Timur Raya antar ulama se-Sumatera.126 Jepang sengaja mempertentangkan kaum adat dengan kaum ulama. Demikian juga halnya dengan cerdik pandai yang mempunyai latar belakang pendidikan luar negeri dianggap sebagai kaki tangan Belanda, meskipun demikian, tenaga mereka tetap dipergunakan dalam administrasi kantor pemerintah.
Pemerintah Jepang memaksa kalangan ulama memfatwakan bahwa perang Asia Timur Raya (Perang Dunia II) sebagai perang sabil.127 Meskipun demikian, Ulama Minangkabau memaknai perang sabil
125 Upaya pendekatan ini tidak hanya terjadi di Minangkabau. Pada Oktober
1942, Jepang melalui Kepala Kantor Urusan Agama di Jawa melakukan pertemuan dengan sejumlah Kiyai yang memimpin pondok pesantren. Hal ini menjadi sarana utama bagi Jepang untuk memobilisasi massa dalam jumlah banyak mengindoktrinisasi pemuda. Pada Desember 1942, 32 orang Kiyai mendapatkan kehormatan untuk diterima oleh Gunseikan di Jakarta. Hal ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri yang tidak pernah didapatkan sebelumnya pada masa kolonialisasi Belanda. M. C. Ricklefs, A
History of Modern Indonesia, 414. 126 M. D. Mansoer, et. all., Sedjarah Minangkabau, 216-217. 127 M. D. Mansoer, et. all., Sedjarah Minangkabau, 218. Hal senada juga
diungkapkan dalam M. C. Ricklefs, A History of Modern Indonesia, 416. Fatwa ini jelas mendapatkan reaksi penolakan keras dari masyarakat. Kaum muslim beranggapan bahwa Jepang, seperti halnya sekutu adalah orang kafir dan peperangan yang dilakukan atas nama mereka tidak dapat dikatakan sebagai perang sabil.
62 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
tersebut dengan memerangi kekuasaan Jepang di Minangkabau. Hal ini terindikasi dari terbentuknya gerakan Gyu Gun.128 Gyu Gun berarti tentara sukarela pembela tanah air dan agama. Gerakan ini dipelopori oleh Shekh Djamil Djambek dan Shekh Daud al Rasuli. Gerakan ini kemudian dipropagandakan oleh Khatib Sulaiman dan Rangkayo Rasuna Said sebagai wakil dari pemuda Islam pada waktu itu. Gerakan ini juga mendapat sokongan penuh dari kalangan cerdik pandai yang mempunyai latar belakang pendidikan barat, seperti Angku Mohammad Syafii dan Angku Abdullah Datuak Rumah Panjang. Gerakan ini disambut hangat oleh kalangan adat yang tergabung dalam Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau (MTKAAM).129 Persatuan yang dibentuk oleh masyarakat Minangkabau dan pergerakan yang dilakukan secara diam-diam ternyata mampu menggagalkan tujuan Jepang untuk menaklukkan Minangkabau seutuhnya. Sebaliknya, Jepang sudah dipaksa menyerah kepada Minangkabau sebelum ia menyerah tanpa syarat kepada tentara sekutu yang datang belakangan.
Permulaan tahun 1944 merupakan titik awal kekalahan Jepang dari tentara sekutu. Hal ini dikarenakan jatuhnya Okinawa di Kepulauan Ryu Kyu ke tangan tentara sekutu. Okinawa kemudian dijadikan sebagai pangkalan udara utama oleh sekutu untuk memudahkan usahanya dalam menghancurkan kota-kota industri dan pusat pertahanan Jepang di negaranya sendiri. Melihat kondisi yang kurang menguntungkan ini, Jepang melalui Perdana Menterinya melakukan kunjungan ke Manila dan Jakarta pada Maret 1945. Tujuannya adalah untuk menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia, Philipina dan Burma. Di Indonesia, dibentuk Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia. Pulau Sumatera diwakili oleh Dr. M. Amir dan Mr. Teuku Mohammad Hasan. Badan ini mengadakan pertemuan pada akhir Mei 1945 di bangunan lama Volksraad Jakarta. Keanggotaannya mewakili sebagian besar pemimpin setengah baya di Jawa yang masih hidup dari semua aliran pemikiran
128 Gyu Gun adalah term yang dipergunakan untuk PETA (Pembela Tanah Air)
yang merupakan organisasi tentara sukarela Indonesia. Berbeda dengan Heiho, PETA tidak menjadi bagian tentara Jepang secara resmi, PETA hanya sebatas pasukan gerilyawan yang bertugas membantu penyerangan terhadap sekutu. Pada masa akhir perang, anggota berjumlah 37.000 orang di Jawa, 1.600 orang di Bali dan 20.000 orang di Sumatera. M. C. Ricklefs, A History of Modern Indonesia, 418.
129 Eksistensi gerakan ini terlihat dalam tokoh-tokoh yang dilibatkan dalam angkatan pertama Gyu Gun. Sebagian besar angkatan pertamanya merupakan putra-putra ulama, tokoh adat dan kalangan cerdik pandai Minangkabau, seperti Mohammad Dahlan Djambek, Datuak Ganto Suaro, Abdul Halim, Ismail Lengah dan masih banyak lainnya. M. D. Mansoer, et. all., Sedjarah Minangkabau, 218.
RELASI ISLAM DAN ADAT DI MINANGKABAU | 63
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
penting.130 Tujuan Jepang melakukan manuver politik internasional seperti ini adalah untuk mengharapkan akan adanya bantuan dari Indonesia seandainya terjadi peperangan dengan sekutu.
Pada Juli 1945, jepang berusaha menyatukan gerakan-gerakan pemuda, Masyumi dan Jawa Hokokai menjadi satu Gerakan Rakyat Baru. Akan tetapi, usaha tersebut gagal karena para pemimpin pemuda menuntut langkah-langkah nasionalitis yang dramatis yang tidak dilakukan oleh gerakan tua yang terlihat ketakutan. Sementara itu dalam BPKI di Jakarta, Soekarno mendesak agar argumennya tentang nasionalisme yang bebas dari agama131 disetujui. Karena konsep ini merupakan satu-satunya dasar yang dapat disepakati pemimpin-pemimpin lainnya, maka usulan Soekarno disetujui.
Pada tanggal 8 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima yang disertai dengan adanya pernyataan perang dari Uni Soviet kepada Jepang. Tentara Uni Soviet langsung menduduki Mansyukwo dan beberapa kawasan Korea Utara. Jepang menjadikan kehancuran kota industri tersebut sebagai alasan utama menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Hal ini juga yang menjadi titik kulminasi berakhirnya Perang Pasifik. Berita kekalahan Jepang dari tentara sekutu tidaklah langsung diketahui oleh rakyat. Namun setelah menyerah tanpa syarat kepada sekutu, Jepang melucuti senjata Gyu Gun dan membebaskan seluruh tawanan romusha dan memulangkannya. Prilaku aneh Jepang ini mengundang kecurigaan tokoh masyarakat, hingga akhirnya tersebar kabar bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Hingga akhirnya proklamasi diproklamirkan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta pada 17 Agustus 1945. Setelah diproklamirkannya kemerdekaan, rakyat masih harus menghadapi kenyataan berat, yakni tidak diakuinya kemerdekaan Indonesia oleh Belanda beserta tentara sekutunya.
Hal yang paling menarik untuk dikaji lebih mendalam pada masa kolonialisasi Jepang adalah upaya pengeyampingan hukum adat dengan memberikan ruang gerak yang lebih leluasa bagi berkembangnya hukum Islam. Hal ini terlihat dalam sejarah peradilan di Indonesia. Pada dasarnya, ketertarikan Jepang terhadap Islam dan memberikan ruang gerak yang lebih leluasa hanyalah karena adanya dorongan motivasi yang lebih subjektif daripada komitmen mereka dalam memberikan integritas hukum Islam atau kemakmuran umat Islam.132 Terkait dengan keberadaan
130 M. C. Ricklefs, A History of Modern Indonesia, 423. 131 M. C. Ricklefs, A History of Modern Indonesia, 424. 132 Ratno Lukito, Islamic Law and Adat Encounter, 54.
64 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
lembaga-lembaga peradilan yang dipisahkan dari kekuasaan eksekutif, pada masa kolonialisasinya Jepang tidak melakukan perubahan yang terlalu signifikan. Hanya saja upaya unifikasi yang dilakukan pada masa itu dibatasi hanya dengan integrasi rasial saja yang disesuaikan dengan pembagian wilayah Indonesia pada waktu itu.
Pemerintahan kolonialiasi Jepang melakukan penggantian nama bagi lembaga-lembaga yuridis di Jawa dan Madura.133 Meskipun demikian, Pengadilan Agama tetap mempunyai fungsi yang sama dengan masa penjajahan Belanda. Pada bulan Juni 1944, ada upaya penghapusan peradilan agama yang diajukan oleh Soepomo. Rekomendasi yang diajukan oleh Soepomo ini diikuti juga dengan adanya saran pemerintahan Jepang pada tanggal 14 April 1945. Saran tersebut bertujuan agar pemerintahan Indonesia memisahkan antara masalah agama dan masalah negara. Solusi yang diberikan terhadap rekomendasi ini adalah pelimpahan kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan di kalangan umat Islam, termasuk di dalamnya berkaitan dengan Pengadilan Agama kepada umat Islam dan pelaksanaannya dilakukan secara personal tanpa ada intervensi dari pihak pemerintahan.134 Namun rekomendasi ini tidak bisa dilaksanakan mengingat kemungkinan adanya perlawanan umat Islam apabila seandainya kebijakan ini diimplementasikan.
Berkaitan dengan penempatan dan eksistensi peradilan adat dengan peradilan agama pada masa kolonialisasi, Daniel S. Lev135 berpendapat bahwa hanya ada dua skenario yang dapat mempengaruhi posisi pengadilan adat. Pertama, jika kontrol terhadap lembaga peradilan tersebut dilakukan oleh penguasa daerah merupakan sumber munculnya konflik sosial. Kedua, jika perlawanan yang terorganisir terhadap lembaga adat dapat terakumulasikan. Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa upaya restrukturisasi lembaga peradilan yang dilakukan pada masa kolonialisasi Jepang hanya bertujuan untuk menghapus simbol kolonialisasi Belanda di Indonesia, sementara
133 Lembaga Pengadilan Agama pada awalnya bernama Priesterraaden
kemudian diganti menjadi Sooryoo Hooin, kemudian pengadilan banding yang pada awalnya bernama Hof vor Islamietische Zaken menjadi Kaikyoo Kootoo Hooin. Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Andan, Sejarah Singkat Peradilan Agama di Indonesia (Surabaya; Bina Ilmu, 1983), 44-46.
134 Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Andan, Sejarah Singkat Peradilan
Agama, 45-46. 135 Daniel S. Lev, “Judicial Unification in Post Colonial Indonesia”, Indonesia
16 (1973): 11. Sebagaimana yang diuraikan kembali dalam Ratno Lukito, Islamic Law
and Adat Encounter, 56.
RELASI ISLAM DAN ADAT DI MINANGKABAU | 65
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
karakteristik struktural mendasar dari masyarakat tidak mengalami perubahan signifikan.
C. Masa Kemerdekaan Hingga Reformasi
Kekosongan kekuasaan terjadi di Indonesia pasca menyerahnya Jepang kepada tentara sekutu hingga mulai terbentuknya dasar Negara Indonesia. Hanya sebagian kecil masyarakat yang mengetahui bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Informasi ini kemudian disebarluaskan melalui siaran radio tidak resmi yang tidak dikuasai oleh Jepang. Berita menyerahnya Jepang dan kemerdekaan Indonesia telah diproklamirkan di Sumatera baru diumumkan secara resmi melalui radio pada tanggal 21 Agustus 1945. Pada masa ini, militer Jepang masih mempunyai beberapa pusat kekuatan di Sumatera sehingga setelah berita ini tersebar di radio resmi, namun penyebaran secara luas dan terang-terangan baru mulai terlaksana pada tanggal 4 September 1945.136
Perubahan status Indonesia dari negara jajahan menjadi sebuah negara merdeka tidak serta merta diikuti dengan pembangunan tatanan hukum secara mutlak dan menyeluruh. Pada masa awal kemerdekaan, kehidupan hukum di Indonesia secara esensial tidak terlalu jauh berbeda dengan kondisi hukum pada masa kolonialisasi Jepang di pulau Jawa.137 Proses pembangunan hukum pada masa ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran elit politik yang sudah berkiprah sejak masa kolonialisasi. Sehingga ide-ide radikal dari golongan bawah tidak mampu menjelma menjadi suatu jargon umum yang mempunyai pengaruh kuat dalam pembentukan hukum.138 Hal ini terlihat dalam pemberlakukan hukum pada masa awal kemerdekaan. Untuk menghindari terjadinya vacuum
power pada masa tersebut, bangsa Indonesia diperkenalkan kembali dengan berbagai aturan hukum yang pernah diberlakukan pada masa kolonialisasi Belanda.
Kebijakan pemerintah kolonial dalam memberlakukan teori receptie telah memicu reaksi keras dari umat Islam di Indonesia. Lebih jauh lagi, Hazairin berpendapat bahwa teori ini tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam dan bertujuan untuk menghalangi kemajuan Islam Indonesia
136 M. D. Mansoer, et. all., Sedjarah Minangkabau, 227-228. Penyebaran berita
ini dimulai setelah adanya pernyataan umum yang disampaikan oleh Mohammad Sjafei bahwa Sumatera mengakui kemerdekaan Indonesia. Pada 1 September 1945, Mohammad Sjafei terpilih menjadi Residen Sumatera Barat pertama. Audrey Kahin, Dari Pemberontakan ke Integrasi, 155.
137 Subekti, Law in Indonesia (Jakarta; Yayasan Proklamasi, 1982), 6. 138 Ratno Lukito, Islamic Law and Adat Encounter, 57.
66 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
serta menyebutnya sebagai teori iblis. Hazairin memunculkan antitesa139 terhadap teori tersebut dengan memperkenalkan teori receptie exit atau yang dikenal juga dengan receptie a contrario. Teori ini menyatakan bahwa hukum adat dapat diberlakukan apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam.140 Efektivitas teori ini terlihat dalam tarik ulur proses penetapan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945.
Pemerintah pusat Republik dibentuk di Jakarta pada akhir Agustus 1945. Pemerintah ini menyetujui konstitusi yang telah dirancang oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebelum menyerahnya Jepang. Melihat kemungkinan perkembangan politik di Indonesia, Angkatan Laut Jepang pernah memperingatkan bahwa orang-orang Kristen yang ada di wilayahnya tidak akan menyetujui peranan istimewa Islam. Hal ini terlihat pada Piagam Jakarta141 dan salah satu ketentuan yang tidak menyaratkan keharusan beragama Islam bagi kepala negara. Diangkatnya Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden pada masa itu didasarkan pada pertimbangan para politisi Jakarta bahwa kedua tokoh ini mempunyai kemampuan untuk berhubungan dengan pihak luar Indonesia.142 Ada beberapa pertimbangan dasar yang mempengaruhi iklim politik hukum pada masa pembentukan hukum di Indonesia.
Terkait dengan kondisi ini, Ratno Lukito berpendapat bahwa perubahan-perubahan politik yang terjadi mampu memberikan pengaruh pada posisi institusi peradilan agama dan adat, walalupun tradisi
139 Kemunculan teori ini diawali dengan penyelesaian kasus sengketa waris
pada Pengadilan Negeri Bandung. Dalam amar putusannya, Pengadilan Negeri Bandung memberikan hak waris sepenuhnya kepada seorang anak angkat dengan mengenyampingkan kedudukan kemenakan laki-laki dan perempuan dari pewaris. Kondisi ini sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan dalam Islam. Menyikapi putusan kontorversial ini, hakim-hakim Islam mengadakan pertemuan dengan para Penghulu di Solo. Pertemuan inilah yang kemudian menjadi titik awal berdirinya Perhimpoenan Penghoeloe dan Pegawainya (PPDP). Daniel S. Lev, Peradilan Agama di
Indonesia (Jakarta: Intermasa, 1980), 20-21. 140 Sayuthi Thalib, Receptio A Contratio, 65-69. 141 Piagam Jakarta sebenarnya merupakan dokumen resmi yang dihasilkan oleh
Panitia Kecil yang dibentuk oleh BPUPKI. Tujuan dibentuknya panitia ini adalah untuk menyusun rumusan di antara dua kekuatan kelompok utama, yaitu kelompok naionalis Islam (Abikusno Tjokrosujoso, Abdulkahar Muzakkir, H. A. Salim, Wakhid Hasjim dan Mr. Ahmad Soebarjo) dan nasionalis sekuler (Soekarno, Mohammad Hatta, Mr. A. A. Maramis dan Mr. Muhammad Yamin). Anhar Gonggong, “Salah Kaprah Pemahaman Terhadap Sejarah Indonesia: Persatuan Majapahit dan Piagam Jakarta – Kemayoritasan Islam”, Menjadi Indonesia: 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara, eds. Komaruddin Hidayat & Ahmad Gaus A.F., (Jakarta: Mizan, 2006), 43-45.
142 M. C. Ricklefs, A History of Modern Indonesia, 430.
RELASI ISLAM DAN ADAT DI MINANGKABAU | 67
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
substanstif kedua sistem hukum ini terbukti tetap tidak terpengaruhi oleh berbagai macam pergolakan politik.143 Untuk mengidentifikasi kondisi sosiologis pada masa ini, beliau memetakannya dalam beberapa kajian tersendiri yang dapat secara rinci mendeskripsikan arah pengembangan hukum di Indonesia, demikian juga halnya dengan relevansi hubungan hukum adat dengan hukum Islam dalam perkembangannya pasca kemerdekaan Indonesia.
Salah satu isu sentral yang mengapung pada masa awal kemerdekaan adalah upaya unifikasi hukum.144 Upaya ini merupakan salah satu usaha untuk menghapuskan semangat hukum kolonial dan pembentukan suatu tatanan hukum baru. Hal ini merupakan tugas berat bagi para sebuah negara yang mempunyai penduduk dengan tingkat heterogenitas tinggi. Tatanan hukum yang sudah ada sangat erat kaitannya dengan sendi-sendi kebudayaan dan kepercayaan agama serta sifat kulturalisme.145 Hal ini berdampak pada tidak efektifnya upaya unifikasi hukum yang didorong oleh ketidakstabilan iklim politik pasca kolonialisasi. Untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum dengan pertimbangan pluralisme hukum yang dipakai oleh masyarakat, maka oleh sebab itu ditetapkanlah Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.
Situasi ini kemudian mengalami pergeseran dengan adanya semangat revolusi. Semangat revolusi mendorong kekuatan nasional untuk meruntuhkan kekuatan kolonial dalam semua perwujudannya. Ide pembangunan hukum nasional semakin mendapat tempat. Hal ini ditandai dengan adanya mobilisasi nasional untuk menggoyangkan kekuatan elit politik lokal. Wujud nyata upaya ini adalah pengadopsian lembaga-lembaga nasional di tingkat masyarakat daerah. Hal ini mempunyai konsekuensi logis dengan tereliminasinya lembaga-lembaga peradilan adat khususnya untuk daerah yang berada di luar pulau Jawa. Eliminasi institusi adat di luar pulau Jawa berjalan perlahan namun pasti seiring dengan adanya mobilisasi sosial yang mendorong ekspansi institusi-institusi nasional.146 Salah satu bentuk upaya ini adalah unifikasi lembaga peradilan. Reorganisasi lembaga peradilan ke dalam satu bentuk peradilan
143 Ratno Lukito, Islamic Law and Adat Encounter, 57-58. 144 Konsep adatrechtpolitiek yang dibangun oleh Cornelis van Vollenhoeven
tidak mampu berkembang dan dipertahankan dalam masa awal kemerdekaan. Semboyan yang dipergunakan dalam negara baru adalah kesatuan, bukan keragaman. Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia: Kesinambungan dan Perubahan (Jakarta: LP3ES, 1990), 433.
145 Ratno Lukito, Islamic Law and Adat Encounter, 59-60. 146 Soetandyo Wignjosoebroto, Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 192-193.
68 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
yang sederhana dan terpusat. Di Sumatera, upaya nasionalisasi lembaga peradilan dan penggantian otoritas kesultanan dengan menghilangkan kekuatan hukum adat mendorong munculnya konflik-konflik berdarah.
Kecenderungan upaya ini dapat terlihat dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1947 pada tanggal 27 Februari 1947. Regulasi ini menegaskan bahwa organisasi dan kewenangan Mahkamah Agung beserta Kejaksaan Agung kembali pada rumusan yang sudah ditetapkan pada 17 Agustus 1945. Penjelasan Undang-undang ini secara nyata menggambarkan keyakinan pihak pemerintahan bahwa unifikasi sistem peradilan merupakan jalan utama untuk menuju kebersatuan bangsa. Regulasi ini semakin dipertegas dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1947 pada tanggal 29 Agustus 1947 yang secara ekspresif menghapuskan eksistensi peradilan adat yang berada di wilayah otonomi Jawa dan Sumatera.
Upaya ini masih terus dilanjutkan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 pada bulan Juni 1948. Meskipun undang-undang ini tidak berlaku dengan efektif karena kembalinya kekuasaan Belanda di Indonesia, namun ide mengenai unifikasi sistem peradilan telah mengakar dalam masyarakat. Pasal 6 dan 7 regulasi ini menyatakan adanya pengakuan terhadap 3 bentuk lembaga peradilan, yaitu; peradilan umum, peradilan administrasi dan peradilan militer dengan hierarki bertingkat seperti yang masih berlaku sampai saat ini. Terhadap regulasi ini, Ratno Lukito berpendapat bahwa telah terjadi keteledoran para arsitek hukum di Indonesia dalam memahami kompleksitas konflik yang terwariskan antara eksponen hukum adat dan hukum Islam karena tidak sedikitpun membahas kedudukan peradilan adat dan peradilan agama.147 Hal ini dapat diperhatikan dari isi regulasi tersebut yang tidak secara tegas menjelaskan kedudukan hukum adat dan hukum Islam.
Berkaitan dengan hal ini, Daniel S. Lev148 mengulasnya secara rinci. Beliau menyatakan bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum adat, pasal 10 undang-undang ini menentukan otoritas hukum penduduk dalam suatu daerah diperbolehkan untuk dilanjutkan dalam menengahi konflik dan kejahatan yang termasuk dalam cakupan living law (hukum yang hidup dalam masyarakat). Penggunaan term yang mempunyai makna ambigu terhadap institusi hukum adat sebagai suatu hukum yang hidup dalam masyarakat dan bukannya secara langsung menggunakan
147 Ratno Lukito, Islamic Law and Adat Encounter, 57-58. 148 Penejelasan lebih lanjut, dalam Daniel S. Lev, “Judicial Unification in Post
Colonial Indonesia”, Indonesia 16 (1973): 21-22. Lihat juga uraian dalam Ratno Lukito, Islamic Law and Adat Encounter, 62-63.
RELASI ISLAM DAN ADAT DI MINANGKABAU | 69
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
term hukum-hukum adat berimplikasi pada berbagai bentuk kekhawatiran yang mulai membebani para pejabat peradilan dan juga beberapa konflik yang muncul. Ambiguitas dalam pemaknaan ini dimaknai seperti dua kutub yang saling berlawanan. Dalam prakteknya, setiap kesempatan muncul selalu selalu dipergunakan oleh pejabat peradilan untuk menyisihkan hukum adat. Pada kenyataannya, penggunaan konsep hukum yang hidup dalam masyarakat ini hanya mengkamuflasekan intensitas ketegangan antara pihak yang menguasai pemerintahan nasional yang baru dengan kekuatan-kekuatan Islam. Sebagai solusi dalam menghadapi masalah ini, pemerintah kemudian berinisiatif untuk mengakui status hukum Islam dan hukum adat guna menghilangkan sumber konflik.149
Usaha unifikasi hukum dan sistem peradilan semakin intensif pasca kembalinya bentuk pemerintahan Indonesia menjadi republik yang berdaulat dari bentuk RIS pada tahun 1949. Unifikasi hukum pada kenyataannya tidak hanya dipahami sebagai suatu bentuk argumentasi sosial atau yuridis semata, namun juga dalam hal kekuasaan politik yang tersentralisasi, sementara itu hukum adat yang sejak awalnya bermakna plural menjadi simbol dari pertahanan otonomi daerah. Isu unifikasi hukum yang muncul pada masa ini mempunyai implikasi luas bahkan sampai satu dekade belakangan ini. Persoalan yang muncul sekarang tidak hanya dibatasi oleh masalah unifikasi hukum vis a vis pluralisme hukum per se, namun lebih jauh dari itu juga melibatkan berbagai argumentasi kecenderungan sentralisasi kekuasaan negara vis a vis desentralisasinya.150 Beranjak dari kondisi ini, dapat dipahami bahwa kondisi dan situasi politik mempunyai peran penting dalam menentukan arah pengembangan hukum.
Angin segar legitimasi eksistensi hukum adat menemukan momentumnya pada saat hangatnya konflik antara Indonesia dan Belanda terkait pembebasan Irian. Berdasarkan hukum, upaya mempertahankan eksistensi hukum adat sebagai semangat dan nilai-nilai asli daerah mendapatkan momentumnya. Salah satu bentuk ini adalah adanya kebijakan penggantian simbol resmi sistem hukum Indonesia. Simbol Dewi Keadilan (Dewi Yustisia) yang merupakan simbol tatanan hukum Eropa diganti dengan lambang pohon beringin yang dalam tradisi jawa menggambarkan makna pengayoman.151 Pada tahun 1960, Majelis
149 Ratno Lukito, Islamic Law and Adat Encounter, 63. 150 Soetandyo Wignjosoebroto, Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional, 202-
203. 151 Soetandyo Wignjosoebroto, Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional, 210-
211.
70 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) telah menetapkan Tap MPRS Nomor II/MPRS/1960 yang secara eksplisit melegitimasi kedudukan hukum adat sebagai suatu sumber pembangunan dan elaborasi hukum Indonesia. Meskipun dalam perjalanannya, konsep yang diusung oleh pemerintah ini juga mengalami pro dan kontra dalam pandangan para ahli.
Antusiasme para ahli dalam upaya membangun kembali hukum di Indonesia sebagai mana yang diamanatkan dalam Tap MPRS Nomor II/MPRS/1960 dapat ditemukan turunannya dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria. Regulasi ini merefleksikan berbagai kesulitan yang ditemui dalam upaya merekonstruksi suatu tatanan hukum yang murni berorientasi nasional. Secara teorinya, hukum adat akan dijadikan sumber hukum utama dan lebih diprioritaskan dalam menyelesaikan perkara-perkara tanah daripada menggunakan ketentuan yang sudah diatur dalam Burgelijk Wetboek (BW). Hal ini merupakan usaha teoritis dalam upaya menghapuskan hukum kolonial. Kondisi ini jauh berbeda dengan praktik yang terjadi di lapangan. Implementasi yang terjadi dalam kondisi sosiologis di lapangan, ternyata masih ditemukan beberapa ketentuan pokok agraria yang diadopsi dari BW itu sendiri. Bahkan ketentuan ini terkesan menghilangkan hak-hak yang berkaitan dengan hukum adat, seperti halnya hak ulayat. Berdasarkan ketentuan dalam regulasi ini, semua tanah menjadi subjek guna menjaga keamanan dan kebersatuan nasional.
Peralihan Orde Lama ke Orde Baru bukanlah masa yang mudah. Konsolidasi Orde Baru sudah barang tentu tidak terlepas dari kondisi yang ditinggalkan Orde Lama. Tidak berarti bahwa seluruh peninggalan Orde Lama dibuang, bahkan secara ideologis justru lebih dipertegas sebagai landasan Orde Baru. Tekad Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.152 Strategi yang dipergunakan oleh Orde Baru dalam dalam upaya melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen adalah dengan memperkenalkan konsep trilogi
152 Ketika Soeharto menguasan panggung perpolitikan dalam kurung waktu ±
32 tahun, meskipun konseptor orde baru menyatakan bahwa mereka melaksanakan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen, namun kekuatan Islam tidak mendapat peluang untuk berkembang. Islam pada masa itu terseingkirkan, meskipun eksistensinya terwakili dalam PPP. Hal ini juga disebabkab oleh pemberlakuan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi setiap partai politik dan organisasi massa. Anhar Gonggong, “Salah Kaprah Pemahaman Terhadap Sejarah Indonesia”, 58.
RELASI ISLAM DAN ADAT DI MINANGKABAU | 71
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
pembangunan.153 Trilogi pembangunan ini diperkenalkan sebagai stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan. Pada masa ini, Soeharto membuat beberapa perubahan mendasar dalam orientasi ideologi serta politik pemerintahan dan kebijakan ekonominya. Pada waktu yang hampir bersamaan, dengan menggunakan peninggalan hukum kolonial sebelumnya yang melandasi penerapan demokrasi terpimpin, Soeharto secara bertahap memberlakukan rezim birokrasi otoriter yang didukung oleh kekuasaan militer. Rezim ini mengebiri eksistensi partai politik, dan sebagai gantinya memberikan penekanan pada rehabilitasi ekonomi.154
Pergantian era kepemimpinan dari masa pemerintahan Orde Lama Soekarno ke era kepemimpinan Orde Baru Soeharto yang disertai dengan pergesaran dalam arena politik berpengaruh terhadap perkembangan sistem hukum Indonesia. Pada era ini, hukum dijadikan sebagai media rekayasa sosial.155 Ide ini begitu cepat popular setelah pada awalnya dimunculkan oleh Mochtar Kusumaatmaja. Ide ini pertama kali disampaikan dalam 28
th International Congress of Orientalist pada tahun
1973. Beliau berargumen bahwa dibutuhkan suatu kombinasi pendekatan sosial dalam studi hukum pada negara-negara berkembang dalam usahanya untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial ekonomi yang dialaminya.156
153 Trilogi pembangunan yang dimaksud adalah; 1) terciptanya stabilitas yang mantap, yang memungkinkan kelangsungan jalannya pembangunan; 2) pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk memperbesar “kue nasional”; dan 3) pemerataan hasil pembangunan untuk memenuhi prinsip keadilan sosial. Penjelasan lebih lanjut lihat dalam Sulastomo, Hari-hari Yang Panjang Transisi Orde lama ke Orde Baru: Sebuah
Memoar (Jakarta: Kompas, 2008), 191-221. 154 Istilah Pancasila yang merupakan salah satu konsep sentral Soekarno pada
masa ini tidak dihapus, namun bentuk demokrasi pancasila mulai mengalami perubahan dari bentuk aslinya yang disesuaikan dengan pokok-pokok dan kebutuhan penguasa yang baru. Hal ini dikamuflasekan dengan pemerintahan berdasarkan mufakat dan bukan kompetisi politik, sehingga karakter demokrasi Pancasila menjadi semakin otoritarian. Audrey Kahin, Dari Pemberontakan ke Integrasi, 397-398.
155 Pada orde lama, hukum diartikan sebagai alat revolusi. Sementara itu pada era orde baru, hukum diasumsikan sebagai untuk pembangunan, hukum sebagai roda penggerak mempercepat pembangunan. Bahkan, lebih jauh dari itu, hukum dipandang nasional sebagai media untuk mencapat tujuan tersebut. Soetandyo Wignjosoebroto, Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional, 224-227.
156 Mochtar Kusumaatmaja, “The Role of Law in Development: The Need For Reform of Legal Education in Developing Countries” dalam Role of Law in Asian
Society, Vol II (1973). Lihat juga Soetandyo Wignjosoebroto, Dari Hukum Kolonial Ke
Hukum Nasional, 231. Dalam keadaan ekonomi yang stabil, Soeharto dan para penasehat dekatnya memulai strategi yang dimaksudkan untuk mengukuhkan kontrol mereka terhadap Indonesia dan rakyatnya. Mereka menghadapi masalah-masalah integrasi nasional dengan menjalankan militerisasi dan sentralisasi yang akan mengatasi setiap
72 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Senada dengan hal ini, Max Webber pernah meyakinkan kita untuk melihat bahwa pertumbuhan sistem hukum modern tidak dapat dilepaskan dari kemunculan industrialisasi yang kapitalis. Sistem hukum yang ada pada masa sekarang ini dikarenakan adanya tuntutan industrialisasi yang kapitalis akan adanya sesuatu tatanan normatif yang mampu mendukung pola kerjanya secara rasional. Dalam sistem normatif (baca: hukum) yang dibutuhkan oleh suatu sistem yang juga mampu memberikan rasionalitas dan prediktabilitas dalam kehidupan ekonomi. Sejak saat itu dapat terlihat adanya sentralisme hukum negara dan semakin tergusurnya jenis hukum lainnya seperti hukum adat.157
Ide yang dilontarkan oleh Mochtar Kusumaatmaja ini terlihat netral dalam menengahi ketegangan yang terjadi antara kaum yang ingin mempertahankan pluralitas hukum dan kaum yang menginginkan unifikasi hukum nasional. Lebih jauh, beliau menegaskan bahwa keputusan tergesa-gesa yang berkaitan dengan pembangunan hukum harus dihindari. Pemerintah harus mempertimbangkan keputusan untuk melanjutkan tradisi hukum kolonial atau menggunakan hukum adat dalam kerangka hukum nasional. Dibutuhkan klasifikasi yang berbeda terhadap bidang hukum yang memungkinkan adanya inovasi dan modifikasi dengan yang tidak mungkin dilakukan modifikasi. Beliau berpendapat bahwa tidak mungkin dilakukan inovasi dan modifikasi terhadap bidang-bidang yang berhubungan dengan kehidupan kultural dan spiritual masyarakat. Sedangkan terhadap beberapa wilayah netral yang diatur oleh hubungan sosial dari pranata kehidupan modern, pemerintah mempunyai keleluasaan untuk mengadopsi hukum yang datang dari luar.158
Pada tahun 1950-an, Mahkamah Agung beserta beberapa pakar hukum seperti Hazairin telah berusaha membangun sejumlah gagasan dan lembaga adat nasional, akan tetapi hanya sedikit. Tidak ada aparat negara pusat setara direktorat yang merumuskan dalil-dalil tentang adat, sementara lembaga yang ada hanya terbatas pada satu atau dua provinsi saja. Lebih jauh lagi, pemerintah Orde Baru menentang gagasan adat sebagai sebuah sistem hukum alternatif.159 Dalam buku-buku resmi, adat
ancaman yang mungkin timbul dari gerakan-gerakan otonomi daerah. Audrey Kahin, Dari Pemberontakan ke Integrasi, 398.
157 Satjipto Rahardjo, Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia (Jakarta: Kompas, 2003), 23.
158 Konsep inilah yang kemudian disebut dengan teori unifikasi hukum selektif oleh Ratno Lukito. Lihat Ratno Lukito, Islamic Law and Adat Encounter, 68.
159 John R. Bowen, “Syariah, Negara dan Norma-norma Sosial di Perancis dan Indonesia”, dalam Dinamika Kontemporer Dalam Masyarakat Islam, ed. Dick van der Meij (Jakarta; INIS, 2003), 111.
RELASI ISLAM DAN ADAT DI MINANGKABAU | 73
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
lebih digambarkan sebagai sebuah upacara dan ritual-ritual daripada kepemilikan tanah dan penyelesaian beberapa konflik yang mungkin saja akan terjadi dalam masyarakat.
Salah satu kondisi sosial yang terjadi di Sumatera Barat adalah adanya penghapusan sistem administrasi pemerintahan nagari yang sudah ada sebelumnya. Upaya reorganisasi pemerintahan pada tingkat yang lebih rendah berakibat pada hilangnya struktur sosial asli masyarakat Minangkabau. Sistem pemerintahan nagari yang sudah ada harus digantikan oleh sistem pemerintahan desa seperti yang berlaku di Pulau Jawa. Pada masa awal pemerintahan Orde Baru, nagari telah diakui memiliki potensi besar dalam pembangunan160 sehingga pemerintah pada tingkat provinsi di Sumatera Barat telah mempersiapkan perangkat guna merealisasikan tujuan ini. Namun dengan disahkannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Sistem Administrasi Pemerintahan Desa, usaha ini kemudian menjadi sia-sia. Regulasi ini memaksakan fungsi dan term desa sebagai unit pemerintahan terkecil dalam pemerintahan, mengatur organisasi internal, fungsi dan prerogatifnya yang seragam161 berdasarkan model desa yang ada di Jawa.
Terkait pelaksanaan undang-undang ini, pemerintah Sumatera Barat pada masa jabatan Gubernur Azwar Anas pada awalnya cenderung untuk memutuskan nagari sebagai suatu kesatuan administrasi desa yang baru. Diakui bahwa keputusan ini akan mempertahankan keserasian antara fungsi administrasi, ekonomi dan budaya dari unit teritorial tradisional kendatipun namanya telah diubah. Akan tetapi nagari menggabungkan wilayah yang lebih luas dan lebih banyak jumlah penduduknya dari unit desa yang ada di daerah Jawa dan daerah lainnya di Indonesia.162 Pada masa jabatan yang kedua di tahun 1983, Gubernur Azwar Anas memberlakukan regulasi yang menetapkan bagian dari nagari, yakni jorong yang menjadi unit desa. Dengan satu lompatan, jumlah desa di Sumatera Barat mengalami perkembangan yang signifikan
160 Mestika Zed, Eddy Utama dan Hasril Chaniago, Sumatera Barat di
Panggung Sejarah 1945-1995 (Padang; Bidang Penerbitan Khusus Panitia Peringatan 50 Tahun Kemerdekaan Indonesia, 1995), 294. Dibandingkan desa, nagari lebih cocok untuk dijadikan model pemerintahan pada tingkat terkecil. Nagari di Minangkabau, meskipun jumlah penduduknya sama dengan jumlah penduduk desa di Jawa,namun nagari memiliki daerah yang lebih luas dan telah cukup berpengalaman dalam penerapan sistem dewan yang pernah dimodifikasi oleh Belanda. Nagari juga menguasai sumber-sumber pendapatan yang lebih memadai. J.D. Legge, Cultural Authorithy and Regional
Autonomy in Indonesia: a Study in Local Administration 1950-1960 (Ithaca: Cornell University Press, 1961), 93-94.
161 Audrey Kahin, Dari Pemberontakan ke Integrasi, 406-407. 162 Audrey Kahin, Dari Pemberontakan ke Integrasi, 408-409.
74 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
dari 543 jumlah nagari menjadi 3.138 jumlah jorong ditambah dengan 408 daerah kota atau kelurahan.163 Akan tetapi, pemecahan nagari ini berimbas pada kehancuran institusi lokal tradisional yang sudah ada sejak beratus tahun sebelumnya.
Konsep unifikasi selektif mempunyai kontribusi penting dalam pembangunan hukum modern era orde baru di Indonesia.164 Dukungan penuh yang diberikan oleh lembaga eksekutif terhadap ide ini mampu meredam ketegangan konflik yang terjadi antara kaum pluralis dengan kelompok uniformis. Dalam upaya meningkatkan taraf perekonomian Indonesia, institusi hukum dipaksa untuk lebih selektif dan berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dan harus lebih akomodatif dengan perkembangan ekonomi. Pada masa ini, hukum sepenuhnya menjadi alat kontrol sosial pemerintah.165 Kondisi ini sangat tidak menguntungkan bagi kalangan yang menyuarakan pluralitas hukum, terlebih lagi dikarenakan semakin berkurangnya para ahli hukum adat.
Sedikit berbeda dengan tantangan yang dialami oleh hukum adat, hukum Islam tidak begitu terpengaruh dengan iklim perubahan peta perpolitikan dan sentralisasi pembangunan hukum Indonesia. Hukum Islam yang lebih nasionalis mampu bertahan lebih baik daripada hukum adat yang bersifat lokal.166 Titik singgung maksimum antara kekuatan agama dengan politik nasional adalah kedudukan dan kekuasaan khusus yang diberikan kepada hakim agama yang dipilih dan ditetapkan oleh negara.167 Di Indonesia, hal ini terlihat jelas dengan eksistensi perjalanan lembaga peradilan agama.
163 Asnawi, “Pembangunan Sumatera Barat”, Sumatera Barat di Panggung
Sejarah 1945-1995, eds. Mestika Zed, Edy Utama dan Hasril Chaniago (Sumatera Barat; Bidang Penerbitan Khusus Panitia Peringatan 50 tahun RI Sumatera barat, 1995), 290-291.
164 Sajuti Thalib, Politik Hukum Baru: Mengenai Kedudukan dan Peranan
Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional (Bandung: Bina Cipta, 1987), 65-67.
165 Ratno Lukito, Islamic Law and Adat Encounter, 68-69. 166 Secara teoritis, posisi hukum adat semakin dilemahkan pada tingkat nasional
dengan adanya 19 wilayah hukum berdasarkan kesamaan adat budaya oleh Cornelis van Vollenhoeven. Ratno Lukito, Islamic Law and Adat Encounter, 68.
167 Pendapat ini dinyatakan oleh Allan Christelow berdasarkan penelitian dan analisisnya terhadap hubungan antara politik dan agama dalam Islam. Penjabaran lebih lanjut lihat Allan Christelow, Muslim Law Courts and the French Colonial State in
Algeria (New Jersey; Princeton University Press, 1985). Hal ini dapat dibenarkan apabila dilihat pada fenomena akomodasi hukum yang tercipta pada beberapa Negara muslim. Ratno Lukito, Islamic Law and Adat Encounter, 69.
RELASI ISLAM DAN ADAT DI MINANGKABAU | 75
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Pada dekade awal kemerdekaan Indonesia, peradilan agama menjalan tugas dan wewenangnya berdasarkan ketetapan pada masa kolonialisme. Usaha untuk meluaskan wilayah yuridiksinya selalu kandas dikarenakan kegagalan usaha reorganisasi sistem peradilan pada masa awal kemerdekaan. Pada masa kolonialiasi Jepang, peradilan agama berada di bawah naungan Kementerian Kehakiman, namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1946 tanggal 25 Maret 1946, beralih ke bawah naungan Kementerian Keagamaan. Pada tahun 1948, berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948, peradilan agama digabungkan ke peradilan umum. Artinya, semua perkara yang melibatkan orang Islam akan di selesaikan oleh hakim muslim di Pengadilan Negeri.168 Adanya agresi militer yang dilakukan oleh Belanda berakibat pada tidak terlaksananya regulasi ini. Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945,169 maka eksistensi Pengadilan Agama tetap berlanjut berdasarkan ketetapan dalam Staatsblad 1882 Nomor 152, terutama bagi wilayah Jawa dan Madura. Pengadilan Agama untuk wilayah di luar pulau Jawa dan Madura kembali dibangun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957.
Perkembangan Pengadilan Agama juga mengalami hambatan pada tatanan akademisi dan praktisi. Teori resepsi yang dikembangkan ahli hukum Belanda ternyata mempengaruhi pemikiran dan sikap para sarjana hukum tamatan Belanda yang bekerja di lembaga kehakiman.170 Sikap antagonisme terhadap eksistensi Pengadilan Agama terlihat dari beberapa pemikiran yang dilontarkan oleh Raden Soepomo ketika menjabat sebagai penasehat pada Departemen Kehakiman.171 Sementara itu, para hakim yang bekerja pada Pengadilan Agama merupakan kaum tradisionalis yang
168 Ratno Lukito, Islamic Law and Adat Encounter, 70. 169 Undang-undang Dasar Republik Indonesia masih memberikan margin of
tolerance melalui eksistensi Aturan Peralihan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kekosongan hukum yang berimbas pada kekacauan kehidupan. Satjipto Rahardjo, Sisi-
sisi Lain Dari Hukum di Indonesia, 24. 170 Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo
bahwa aktivitas pengembangan hukum yang berskala besar akan melibatkan banyak pihak, terutama pembuat dan penegak hukum. Demikian juga halnya dengan upaya pembentukan hukum itu sendiri yang tidak boleh mengabaikan aspek manusia sebagai sosok sentral dari hukum itu sendiri. Satjipto Rahardjo, Sisi-sisi Lain Hukum di Indonesia, 5-6. Kondisi ini jelas-jelas mempengaruhi subjektivitas dalam pembuatan dan penerapan hukum itu sendiri, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya tarik ulur dari polaritas kelompok yang berbeda.
171 Deliar Noer, The Administration of Islam in Indonesia (Itacha; Cornell University, 1978), 45, lihat juga dalam Ratno Lukito, Islamic Law and Adat Encounter, 71.
76 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
hanya memahami mazhab fiqh Shafii klasik. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan yang tinggi antara kualitas dan pengetahuan hakim-hakim yang terlibat dalam lembaga peradilan. Kesenjangan ini juga menunjukkan ketidakseimbangan kekuatan dalam ketegangan antara kaum muslim dengan kelompok nasionalis.
Puncak ketegangan antara kedua kelompok ini terlihat pada ditetapkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 1970 sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964. Dalam ketentuan pasal 10 Undang-undang ini, dinyatakan bahwa kekuasaan peradilan dijalankan oleh lembaga-lembaga peradilan dalam bentuk pengadilan agama, militer dan administrasi. Meskipun regulasi ini mengakui keberadaan pengadilan agama dalam lingkungan peradilan, namun dalam tatanan praksisnya ternyata tidak pengadilan agama tidaklah mempunyai kewenangan sepenuhnya terhadap perkara yang telah diputuskannya. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan yang menyatakan bahwa setiap putusan Pengadilan Agama harus diratifikasi oleh Pengadilan Negeri sebelum diimplementasikan secara resmi. Fiat of execution (executoire verklaring) dibutuhkan apabila pihak yang berperkara tidak secara sukarela tunduk pada putusan Pengadilan Agama.Ketentuan ini menunjukkan adanya superioritas Pengadilan Negeri terhadap Pengadilan Agama, sehingga tidak sedikit hakim-hakim Pengadilan Negeri yang memandang rendah hakim-hakim pada Pengadilan Agama. Hal inilah yang mengundang reaksi keras dari Hazairin172 terhadap ketidakseimbangan kedudukan lembaga peradilan.
Baik pemerintahan Soekarno maupun pemerintahan Soeharto sama-sama menekankan pentingnya suatu kesatuan sistem hukum, sebagian besar untuk menjamin pengawasan ideologi dan politik yang lebih besar terhadap lembaga-lembaga sosial dan politik. Tapi mereka pun berusaha menghindar dari upaya mengasingkan tokoh muslim yang menuntut penerapan hukum Islam secara lebih efektif.173 Ditetapkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama ternyata cukup mengejutkan beberapa pihak. Regulasi ini memberikan perubahan baru terhadap kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama. Pengesahan regulasi ini menunjukkan keberhasilan usaha kelompok muslim dalam membentuk suatu lembaga peradilan modern. Hal ini
172 Hazairin dikenal sebagai tokoh yang sangat menentang dan mengkritik teori
resepsi yang dilontarkan oleh ahli hukum Belanda. Bahkan, beliau menyebut teori resepsi ini dengan “teori iblis”, penjelasan lebih lanjut, lihat Hazairin, Hukum
Kekeluargaan Nasional (Jakarta; Tintamas, 1982), 7-10. 173 John R. Bowen, “Syariah, Negara dan Norma-norma Sosial”, 108-109.
RELASI ISLAM DAN ADAT DI MINANGKABAU | 77
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
terlihat dari penyamaan nama bagi semua tingkatan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Pengakuan kedudukan ini juga disertai dengan perluasan yuridiksi kasus yang boleh diselesaikannya. Satu hal yang paling penting dari regulasi ini adalah adanya kedudukan yang sama antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri, sehingga executoire
verklaring tidak diperlukan lagi. Keberadaan undang-undang ini memperluas yuridiksi dan memperbesar kekuasaan penyelenggaraan pengadilan agama, bahkan ketika undang-undang ini dan beberapa undang-undang lainnya menjadikan sistem hukum Indonesia lebih terintegrasi secara rapat, sehingga dengan demikian tunduk pada pengawasan negara yang lebih besar.
Perkembangan ranah ketegangan antara kalangan muslim dengan kalangan nasionalis mulai mengalami pergeseran. Setelah ditetapkannya Undang-undang yang secara khusus mengenai kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama, diskusi-diskusi yang muncul lebih senderung terfokus pada pemikiran-pemikiran untuk mengintegrasikan Islam ke sistem ideologi negara.174 Pada masa ini, kekuatan Islam dalam perpolitikan boleh saja mengalami kemunduran, namun kekuatan kulturalnya mempunyai pengaruh yang kuat terhadap iklim politik kontemporer Indonesia.
Pola baru pengembangan kebijakan hukum ini mengundang reaksi dan pergolakan dari berbagai pihak, seperti dalam pelembagaan hukum adat dan hukum Islam. Berbagai kritik terhadap kebijaksanaan ini didasarkan pada argumen bahwa lembaga-lembaga peradilan tersebut akan berafiliasi dengan kekuasaan lokal yang berada di luar kekuasaan politik formal pemerintahan pusat. Terlepas dari pergolakan tersebut, kedua eksponen ini mempunyai pengaruh kuat dalam upaya legislasi regulasi modern dan dalam upaya pemecahan masalah kontemporer di Indonesia, terlebih lagi dalam masalah hukum keluarga. Simbiosis antara kedua sistem hukum juga dipengaruhi oleh pemikiran tokoh-tokoh Islam yang sejak awal kemerdekaan sudah berupaya untuk merekonstruksi pemahaman baru terhadap hukum Islam yang diderivikasikan dari nilai-nilai lokal masyarakat Indonesia.
174 B. J. Boland, The Struggle of Islam in Modern Indonesia (Nijhoff; The
Hauge, 1982), 159.
BAB III IDENTITAS SOSIAL DALAM DEMOKRATISASI
PEMERINTAHAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA
Bagian ini merupakan pemaparan tentang bentuk-bentuk dan perubahan sistem hukum di Indonesia serta pelaksanaan otonomi pada tingkat daerah. Eksistensi berbagai regulasi tersebut memberikan peluang dan bahkan mempunyai peranan penting dalam kelangsungan pola interaksi hubungan antara hukum adat dengan hukum Islam. Kondisi sosial politik pada pemerintahan pusat sangat mempengaruhi iklim pemerintahan pada tingkat daerah. Pergantian rezim pemerintahan diikuti dengan pergantian regulasi membawa dampak hebat terhadap eksistensi dan pelaksanaan hukum adat dan hukum Islam terkhusus pada tingkat regional daerah.
A. Identitas Sosial Masyarakat Minangkabau
Identifikasi sosial merupakan sebuah konsep kunci dalam upaya membentuk sebuah teori tentang proses sosial.1 Identitas sosial dapat dipergunakan untuk menjelaskan struktur individu yang dimaknai sebagai kategorisasi keanggotaan, karakter hubungan inter-grup atau hubungan individu terhadap struktur sosial yang lebih luas. Dalam perspektif sosiologi,2 identitas sosial lebih diasosiasikan dengan konsep yang berasal dari tradisi interaksi simbolis.
Kajian mengenai identitas sosial masyarakat hukum adat Minangkabau tidak dapat dilepaskan dari konsepsi adat.3 Masyarakat hukum adat Minangkabau memaknai adat dengan cara yang berbeda.
1 Kay Deaux, “Models, Meanings and Motivation” dalam Social Identity
Processes, eds. Dora Capozza dan Rupert Brown (London: Sage Publications, 2000), 1. 2 Kajian lebih lanjut terkait perkembangan interaksi simbolis dapat ditemukan
dalam Peter J. Burke dan Jan E. Stets, Identity Theory (New York: Oxford University Press, 2009), 18-32.
3 Gregory Mark Simon, Caged in on the Outside: Identity, Morality and Self in an Indonesian Islamic Community (Disertasi University of California, San Diego: 2007), 73.
80 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Konsepsi adat difokuskan pada pembangunan institusi sosial, sementara itu karakteristik masyarakatnya terkait dengan kecenderungan cara-cara yang ditempuh dalam memberdayakan institusi sosial itu sendiri. Dalam masyarakat Minangkabau, penekanan menuju integrasi sosial seperti halnya penekanan menuju otonomi direalisasikan dalam pengalaman individual dan representasi budaya yang kuat.4
Politik identitas di Indonesia lebih terkait dengan masalah etnisitas, agama, ideologi dan kepentingan-kepentingan lokal yang diwakili pada umumnya oleh para elit dengan artikulasinya masing-masing.5 Abstraksi identitas sosial nilai-nilai adat masyarakat Minangkabau terjabarkan dalam sistem pemerintahan yang dipergunakan institusi sosial asli nagari. Sistem pemerintahan asli nagari yang menggunakan konsep poliarki mencerminkan keseimbangan nilai-nilai dimensi ideal masyarakat Minangkabau.6 Keunikan inilah yang menjadi bentuk identitas sosial yang dipertahankan dan direvitalisasi pada masa otonomi daerah. Kondisi ini berhubungan dengan nilai-nilai penerapan demokrasi kontemporer dalam multikulturalisme7 yang semakin berkembang dewasa ini. Pada dasarnya, demokrasi mempunyai banyak pemaknaan. Adanya legalitas terhadap sistem pemerintahan nagari pada dasarnya merupakan bentuk pengakuan terhadap HAM Kultural yang berada dalam kebhinekaan masyarakat.
Demokrasi haruslah menjunjung tinggi mayoritas, namun bukan mayoritasisme.8 Merujuk pada pendapat Nurcholis Madjid,9 secara
4 Gregory Mark Simon, Caged In on the Outside, 612-613. 5 Gerakan pemekaran daerah dapat dipandang sebagai salah satu wujud dari
gerakan politik identitas tersebut karena isu-isu tentang keadilan dan pembangunan daerah menjadi sangat sentral. Ahmad Syafii Maarif, “Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Indonesia”, dalam Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita, eds. Ahmad Syafii Maarif, et. all. (Jakarta: Democracy Project, 2012), edisi digital, 3.
6 Dimensi ideal dalam karakter masyarakat Minangkabau digambarkan dengan nilai-nilai kerendahan hati, kesalehan, dan penghormatan terhadap adat tradisional yang mencirikan realiasasi adat. Keterangan lebih lanjut bisa disimak dalam Gregory Mark Simon, Caged in on the Outside, 75.
7 Kajian lebih lanjut tentang eksistensi demokrasi multikultural dapat disimak dalam Fred Dallmayr, “Democracy and Multiculturalism’, dalam Democracy and
Difference: Contesting the Boundaries of the Political, ed. Seyla Benhabib (New Jersey: Princeton University Press, 1996), 278-294.
8 Sukron Kamil, Demokrasi Dalam Lintasan Sejarah Islam: Dari Demokrasi Klasik Hingga Kontemporer (Tesis Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1999), 181.
9 Nurcholis Madjid, “Demokrasi dan Demokratisasi”, dalam Demokratisasi
Politik, Ekonomi dan Budaya: Pengalaman Indonesia Masa Orba, ed. Elza Peldi Taher (Jakarta: Paramadina, 1994), 217.
IDENTITAS SOSIAL DALAM DEMOKRATISASI ... | 81
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
sederhana demokrasi dimaknai dengan majority rule, minority right. Demokrasi harus mengakui adanya legalitas nilai-nilai peradaban dan HAM Kultural dalam masyarakat. Proses dinamisasi demokrasi di Indonesia yang secara tidak langsung mempengaruhi pengakuan system pemerintahan nagari masyarakat hukum adat Minangkabau di Sumatera Barat diawali dengan kejatuhan rezim pemerintahan Orde Baru Soeharto. Dalam rentang waktu antara Maret dan Mei 1998, kestabilan politik Indonesia yang semu menjadi sangat kacau ketika serangkaian aksi mahasiswa menyerukan reformasi sistem politik dan ekonomi. Aksi ini memuncak dengan menuntut mundur Presiden Soeharto disertai dengan desakan pelaksanaan sidang MPR guna memilih penggantinya. Tuntutan reformasi semakin meningkat seiring semakin memburuknya kondisi perekonomian. Amin Rais merupakan tokoh yang paling menonjol dalam upaya pengecaman kondisi ini. Demonstrasi yang dilakukan mahasiswa semakin marak terjadi, namun ABRI memberikan keleluasaan mahasiswa yang berdemonstrasi asalkan dilakukan di dalam area kampus masing-masing.
Demonstrasi yang dilakukan mahasiswa semakin membesar dan mencapai titik klimaksnya pada 12 Mei 1998 yang ditandai dengan adanya penembakan terhadap 4 orang demonstran di Universitas Trisakti Jakarta. Penembakan terhadap 4 orang demonstran ini pada akhirnya menjadi titik balik seiring semakin memburuknya kondisi sosial ekonomi, kebrutalan ABRI, korupsi rezim dan kemustahilan akan adanya reformasi. Kerusuhan terjadi di beberapa tempat, lebih dari seribu orang tewas di Jakarta pada kerusuhan 13-15 Mei. Dalam kondisi seperti ini, Soeharto pergi ke Kairo untuk menghadiri konfrensi puncak pada tanggal 7 Mei 1998 dan kembali ke tanah air pada tanggal 15 Mei 1998. Setelah Soeharto kembali berada di Jakarta, kondisi sosial ekonomi semakin kacau bahkan MPR dan ABRI siap mendukung diadakannya sidang istimewa untuk memilih presiden yang baru.
Golkar juga mempunyai pandangan yang sama terhadap semakin memburuknya kondisi ini. Mahasiswa sudah menduduki gedung MPR tanpa ada yang berani megusirnya. Amien Rais mempunyai peran menonjol dalam menuntut berakhirnya masa pemerintahan Soeharto. Pada tanggal 18 Mei 1998, Harmoko selaku Ketua MPR secara terang-terangan meminta Soeharto untuk mengundurkan diri demi kepentingan nasional. Pada 19 Mei 1998, Soeharto bertemu dengan para tokoh Islam terkemuka seperti Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Madjid guna meminta pendapat perihal keharusannya untuk mundur dari jabatan sebagai presiden.
82 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Soeharto kemudian mengumumkan bahwa dia akan mengawal reformasi dan akan mengakhiri masa jabatannya setelah pemilu diadakan. Namun segala bentuk tawaran yang masih melibatkannya sebagai presiden ditolak. Bahkan usahanya untuk mempertahankan jabatan dengan membentuk kabinet reformasi pada tanggal 20 Mei 1998 gagal dikarenakan 14 orang menteri yang ditunjuk menolak untuk bergabung dengan kabinet tersebut. Keesokan harinya tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya di Istana Negara. Wakil presiden B.J. Habibie segera disumpah sebagai Presiden Indonesia yang ke-3. Wiranto kemudian mengumumkan bahwa ABRI tetap satu dan akan mendukung presiden yang baru.
B.J. Habibie menggantikan Soeharto sebagai presiden dengan 5 isu besar10 yang harus dihadapinya. Pasca jatuhnya pemerintahan orde baru, serangkaian kerusuhan sosial, kesengsaraan dan penindasan yang terjadi pada masa Soeharto telah meningkatkan rasa identitas sosial dalam kadar yang mampu mebahayakan keutuhan bangsa. Tiga daerah utama tersebut adalah Aceh, Irian Jaya dan Timor Timur. Menanggapi hal ini, B.J. Habibie membebaskan para tahanan politik Timor Timur dan menjanjikan status istimewa yang belum ditentukan bagi mereka. Namun tawaran ini ditolak oleh Ramos Horta beserta anggota kelompoknya. Pada Januari 1999, Ali Alatas selaku Menteri Dalam Negeri mengumumkan bahwa apabila tawaran otonomi bagi Timor Timur tidak diterima, maka propinsi itu diberikan kemerdekaan.11 Kebijakan ini tidak begitu mendapat dukungan dari kalangan politikus nasional, seperti Megawati dan Abdurrahman Wahid.
Pemilu bebas untuk pertama kalinya di Indonesia dilaksanakan pada April 1999 diikuti oleh 48 partai yang terdaftar. Pada pemilihan ini, Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Presiden dengan Megawati Soekarno Putri sebagai wakilnya. Pada masa awal pemerintahannya, Abdurrahmah Wahid menunjukkan gabungan dari harapan, janji, visi,
10 5 isu besar yang dimaksud adalah; masa depan reformasi, masa depan ABRI, masa depan daerah-daerah yang ingin melepaskan diri dari Indonesia, masa depan Soeharto dan masa depan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. M. C. Ricklefs, A
History of Modern Indonesia Since c. 1200 (Jakarta: Serambi, 2001), ed-3, 655-656. Di antara beberapa isu tersebut, yang menjadi fokus dalam bahasan tesis ini adalah masa depan reformasi yang nantinya membawa pengaruh pada berkembangnya asas desentralisasi kewenangan dan otonomi daerah.
11 Ali Alatas dalam kapasitasnya selaku Menteri Luar Negeri sebelumnya pernah menjanjikan bahwa status daerah istimewa untuk Timor Timur akan jauh berbeda dengan status daerah istimewa seperti yang diperuntukkan bagi Aceh dan Yogyakarta, hanya saja statusnya masih berada dalam konteks Negara kesatuan, bukan federal Republik Indonesia. M. C. Ricklefs, A History of Modern Indonesia, 660-661
IDENTITAS SOSIAL DALAM DEMOKRATISASI ... | 83
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
kebingungan dan kekecewaan. Abdurrahman Wahid lebih cenderung mendorong pluralisme dan keterbukaan.12 Beberapa hal yang menjadi catatan penting selama pemerintahan beliau adalah pendapat untuk memberikan referendum kepada Aceh namun tidak menyertakan pilihan untuk memisahkan diri.
Tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia pada masa ini adalah upaya pemulihan negara hukum. Institusi hukum dan polisi sudah begitu korup pada masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto dan hanya mengalami sedikit perbaikan pada masa pemerintahan B.J. Habibie sehingga hampir seluruh sistem hukum dirombak. Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid berakhir pada Juli 2001. Beliau berusaha membekukan lembaga perwakilan melalui dekrit guna menghindari kemungkinan turun jabatan, namun tidak ada pihak yang menghiraukan. MPR mengadakan sidang istimewa dan memberhentikan Abdurrahman Wahid serta melantik Megawati sebagai Presiden Indonesia yang kelima hingga pemilu yang dijadwalkan pada tahun 2004.
Pada masa pemerintahan Megawati, masih ada beberapa daerah yang ingin menambah otonomi mereka, bahkan ada yang ingin memisahkan diri dari Indonesia seperti Aceh dan Papua. Pada masa ini juga demokrasi mengakar dengan mengesankan. Tahun 2004 merupakan tahun pemilihan yang dilaksanakan secara langsung. Dari pemilihan ini, Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai Presiden Indonesia yang keenam dengan wakilnya Jusuf Kalla. Pada tanggal 20 Oktober 2004, pasangan ini dilantik dengan amanat rakyat yang paling kuat sepanjang sejarah.
B. Desentralisasi Kekuasaan dan Kebijakan Otonomi Daerah
Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menjatuhkan pilihannya pada desentralisasi.13 Hal ini terlihat dalam Pembukaan
12 Hal ini terlihat dari kebijakan untuk memberikan kebebasan bagi umat Cina
Konfusius untuk melakukan perayaan secara terbuka. M. C. Ricklefs, A Historyof
Modern Indonesia, 671. 13 Desentralisasi dalam konteks ini diartikan dalam sebuah pengertian yang
luas, mencakup political decentralization dan administrative decentralization sesuai dengan konsep yang pernah diusung oleh Gabriel U. Iglesias. Menurutnya, political
decentralization akan melahirkan daerah-daerah otonom, sedangkan administrative decentralization adalah istilah lain dari local state government yang melahirkan wilayah-wilayah administratif. Gabriel U. Iglesias, Regionalization and Regional Development in
the Philiphines (Manila: UP-CPA, 1978), 14. Lihat juga penjelasan dalam Josef Riwo Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-
faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), cet-10, 2. Perdebatan seputar hal ini juga terlihat dalam pemaknaan desentralisasi
84 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Undang-undang Dasar 1945 dengan perumusan yang umum dan samar.14 Perumusan gagasan Negara Kesatuan sebagai suatu ketentuan hukun yang berlaku dapat ditemukan dalam pasal 1 UUD 1945 beserta penjelasannya. Demikian juga halnya dengan kedudukan pemerintah yang dapat diperhatikan dalam pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya.
Sehubungan dengan asas Negara Kesatuan yang disentraliasikan, maka yang memegang kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara adalah pemerintah pusat tanpa ada gangguan dari suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Dalam suatu Negara kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat sedemikian rupa, sehingga urusan-urusan negara dalam negara kesatuan tetap menjadi satu kebulatan dan pemerintah pusat memepunyai kedudukan sebagai pemerintah tertinggi.15 Hal ini mengindikasikan bahwa dalam negara kesatuan yang didesentralisasikan, pemerintah pusat tetap mempunyai hak untuk mengawasi daerah-daerah otonom.
Alasan utama dianutnya asas desentralisasi ini adalah guna tercapainya efektivitas pemeritahan dan untuk menjamin terlaksananya demokrasi pada tingkat bawah dan dari bawah. Pelaksanaan desentralisasi akan membawa efektivitas dalam pemerintahan.16 Hal ini disebabkan pada wilayah negara yang terbagi dalam berbagai satuan daerah yang masing-masingnya mempunyai karakteristik sendiri dan berbeda satu sama lainnya. Perbedaan dalam sifat-sifat khusus ini disebabkan oleh faktor geografis, adat istiadat, kehidupan ekonomi, tingkat pendidikan dan lain sebagainya.
Sebagai akibat dari pelaksanaan desentralisasi, terbentuklah daerah-daerah otonom. Pada awalnya, daerah otonom atau daerah berotonomi mempunyai peraturan sendiri atau mempunyai hak dan kewenangan untuk membuat peraturan sendiri. Pemaknaan term ini kemudian berkembang dan seringkali dimaknai sebagai pemerintahan sebagai sebuah devolusi. Silahkan bandingkan antara Maddick, Democracy,
Decentralization and Development (Bombay: Asia Publishing House, 1963), Brian Smith, Decentralization (London: George Allen and Unwin, 1985) dengan Philip Mawhood, Local Government in the Third World (Chicester: John Wisely and Sons, 1983). Lihat juga Riswandha Imawan, “Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance”, dalam Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah, ed. Syamsuddin Haris (Jakarta: LIPI Press, 2005), 40-41.
14 M. Solly Lubis, Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan
Mengenai Pemerintahan Daerah (Bandung: Alumni, 1974), 14. 15 M. Solly Lubis, Pergeseran Garis Politik, 16-17. 16 Josef Riwo Kaho, Prospek Otonomi Daerah, cet-10, 10.
IDENTITAS SOSIAL DALAM DEMOKRATISASI ... | 85
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
sendiri. Pemerintahan sendiri ini meliputi pengaturan atau perundang-undangan sendiri, pelaksanaan sendiri dalam batas-batas tertentu.
Banyak ahli yang berpendapat bahwa konsep desentralisasi dan demokrasi merupakan konsep-konsep yang kompleks.17 Pemahaman terhadap konsep dan teori dari kedua eksponen tersebut menjadi sangat penting. Sejak proklamasi kemerdekaan, Negara Republik Indonesia telah menerapkan bahwa landasan konstitusional Negara ini adalah ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945, yang memuat berbagai aturan dalam hal-hal yang mencakup konstitusi.18
Pada rezim orde baru, Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional bersifat rigid,19 sehingga tidak dapat dilakukan perubahan terhadap pasal-pasal yang termuat di dalamnya. Tujuan utamanya untuk mempertahankan bentuk kekuatan pemerintahan pada masa orde baru. Berbekal hal tersebut, pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan keinginan pemerintah yang berkuasa. Pada masa ini, pemerintah menerapkan konsep desakralisasi Undang-undang Dasar 1945 sehingga tidak seorang pun yang sanggup untuk melakukan perubahan terhadap isi Undang-undang Dasar 1945.20 Ketika arus reformasi bergulir pada tahun 1998, tuntutan dari berbagai pihak semakin menguat untuk diadakan beberapa perubahan dalam Undang-undang Dasar 1945. Pada saat Sidang Umum MPR pada tahun 1999, MPR di bawah pimpinan Amien Rais mulai melakukan amandemen terhadap beberapa pasal Undang-undang Dasar 194521 yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi faktual kehidupan demokratisasi ketatanegaraan pada saat itu.
17 Lihat Furniss N., “The Practical Significance of Decentralization”, The
Journal of Politics, Volume 36 Nomor 3 (1974), 961. Lihat juga Dryzek J.S., “Political Inclusion and the Dynamic of Democratization”, dalam The American Political Science
Review, Volume 90 Nomor 3 (1996): 475-487. Simak juga uraian Mudiayati Rahmatunnisa, “Desentralisasi dan Demokrasi”, Governance, Volume 1 Nomor 2 (2011): 1.
18 Sekumpulan norma hukum yang yang mengatur alokasi fungsi, kekuasaan, serta tugas berbagai lembaga negara serta menentukan hubungan antara lembaga-lembaga tersebut dengan rakyat. Moh. Mahfud M.D., Dasar dan Struktur
Ketatanegaraan Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 2001), 71. 19 Konstitusi apabila dilihat dari sifatnya dapat dikelompokkan menjadi 2
bentuk. Pertama, konstitusi rigid, yang sulit dilakukan perubahan. Kedua, konstitusi fleksibel membuka peluang untuk dilakukan perubahan. Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi (Bandung: Alumni, 2006), 80.
20 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, 2002), 1.
21 Selama periode 1999-2004, MPR berhasil melakukan 4 kali amandemen, yaitu; Perubahan I (19 Oktober 1999), Perubahan II (18 Agustus 2000), Perubahan III (10 November 2001) dan Perubahan IV (10 Agustus 2001). Tidak dapat dipungkiri
86 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa dengan berbagai kearifan lokal yang berbeda-beda. Sistem pemerintahan orde baru yang terlalu menonjolkan ciri sentralisasi kekuasaan22 berefek pada kemunculan berbagai ide pada masa transisi. Hal ini juga yang mendorong munculnya ide untuk menggunakan sistem negara federasi sebagai alternatif terbaik dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Pada dasarnya, perdebatan mengenai pilihan penggunaan bentuk negara federalisme atau kesatuan23 bukanlah harga mati. Hal ini dikarenakan masih ada kemungkinan untuk menerapkan model-model lain dalam pemerintahan. Akan tetapi, nampaknya pemerintah sudah sedemikian rupa berupaya untuk tetap mempertahankan format negara kesatuan sehingga alternatif bentuk negara lainnya sangat sulit untuk dimunculkan.
Kondisi ini juga didorong oleh kekuatan politik pada masa transisi yang tidak mendukung terhadap kemungkinan penerapan sistem pemerintahan yang federalistik.24 Penerapan konsep negara kesatuan lebih tepat dari pada bentuk negara federal dalam masyarakat yang mempunyai tingkat fragmentasi tinggi dan pembilahan sosial yang bersifat kumulatif-konsolidatif.25 Di samping itu, pemilihan bentuk sebuah negara sangat
bahwa Amandemen UUD 1945 merupakan revolusi damai dalam upaya reaktualisasi konstitusi Republik Indonesia dalam menyongsong era globalisasi. B.N. Marbun, Otonomi Daerah 1945-2010: Proses & Realita Perkembangan Otda Sejak Zaman
Kolonial Sampai Saat Ini (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010), 17. 22 Pada masa orde baru, tidak ada satupun pemikiran yang dikembangkan
mengingat konsekuensi yang harus dihadapi nantinya, seperti halnya konsekuensi politik. Utang Rosidin, Otonomi Daerah dan Desentralisasi (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 43.
23 Perbedaan pendapat mengenai negara federal dan negara kesatuan berjalan seiring dengan kontroversi demokratisasi lainnya seperti sistem parlementerisme dan presidensialisme, sistem pemerintahan distrik dan proporsional. Perbincangan mengenai hal ini juga dilatarbelakangi oleh aspirasi otonomi dan kemandirian yang mencuat di berbagai daerah seperti Timor Timur, Aceh, Irian Jaya dan lain sebagainya. Samsu Rizal Panggabean, “Federalisasi dan Demokratisasi Indonesia”, JSP, Volume 1 Nomor 3 (1998). Makalah ini juga pernah dipresentasikan dalam Seminar Nasional bertajuk “Membangun Indonesia Baru: Suatu Pendekatan Konstitusional dan Politik” yang diadakan di Fakultas Hukum UGM pada 31 Agustus 1998.
24 Syaukani, et. all., Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 2.
25 Sebuah negara yang mempunyai tingkat heomogenitas tinggi tidaklah mengalami kesulitan dalam menerapkan bentuk negara federasi mengingat klasifikasi derajat pembilahan sosialnya. Sebaliknya, pada negara yang mempunyai heterogenitas tinggi dan fragmentasi sosial tinggi dalam pemerintahannya membutuhkan sebuah pemerintahan nasional yang kuat. Syaukani, et. all., Otonomi Daerah, 3.
IDENTITAS SOSIAL DALAM DEMOKRATISASI ... | 87
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
erat kaitannya dengan struktur sosial dan etnisitas masyarakat yang ada dalam negara tersebut.
Hal menarik dari adanya upaya amandemen yang dilakukan MPR adalah bentuk negara kesatuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 Undang-undang Dasar 1945. Pasal ini merupakan pasal yang tidak mengalami perubahan sedikitpun dalam 4 tahapan amandemen. Hal ini mengindikasikan bahwa Negara Republik Indonesia dibangun dalam sebuah kerangka kesaturan (unitary) dan bukan bentuk federasi.26 Negara kesatuan adalah suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Sebuah Negara berdaulat hanya mempunyai satu pemerintahan (pusat) di seluruh wilayah negara yang mengatur seluruh daerah. Makna kesatuan dalam hal ini adalah adanya perbedaan tingkatan antara kekuasaan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kekuasaan pemerintah pusat adalah kekuasaan yang paling menonjol dalam sebuah negara. Sedangkan kekuasaan pemerintah daerah bersifat derivatif27 dan seringkali diwujudkan dalam bentuk otonomi luas. Di sisi lain, negara kesatuan juga bertransformasi dalam dua bentuk.28 Pertama, negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, di mana segala sesuatu yang ada di dalam negara diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakannya. Kedua, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi dimana daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah).
Otonomi atau autonomy berasal dari gabungan dua suku kata dalam bahasa Yunani, yakni; auto yang berarti sendiri dan nomous yang berarti hukum atau peraturan.29 Otonomi mengandung pengertian pengaturan sendiri (selfregelling), pemerintahan sendiri (selfbestuur). artinya, di balik konsep otonomi terdapat makna kemandirian.30 Secara sederhana, otonomi dapat dimaknai dengan pemerintah yang mampu menyelenggarakan pemerintahan, yang dituangkan dalam bentuk peraturan sendiri dan sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Otonomi daerah merupakan hak untuk mengatur urusan-urusan daerah dan juga
26 Utang Rosidin, Otonomi Daerah, 32. 27 Derivatif yang dimaksud di sini adalah bersifat tidak langsung. Lihat
penjabaran lebih rinci dalam Moh. Kurnadi dan Bintan R. Saragih, Ilmu Negara (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 207.
28 C.S.T. Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 3. Lihat juga dalam Riwu Kaho, Analisa Hubungan Pemerintah, 3.
29 Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), 33.
30 Ade Saptomo, Hukum dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat
Nusantara (Jakarta: Grasindo, 2010), 1.
88 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
menyesuaikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengannya. Otonomi berarti suatu kondisi atau ciri untuk tidak dikontrol oleh pihak lain maupun kekuatan dari luar. Secara sederhana, otonomi dapat dimaknai dengan sebuah kekuasaan dalam bentuk hak dan kewenangan serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai keadaan dan kemampuan daerahnya sebagai wujud manifestasi dari desentralisasi atau devolusi.31
Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan yang sebelumnya tersentralisasi pada pemerintahan pusat. Dalam proses desentralisasi, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan ke pemerintah daerah sebagaimana mestinya sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Kebijakan otonomi dan desentralisasi ini dinilai sangat penting, terutama untuk menjamin agar proses integrasi nasional dapat terpelihara sebaik-baiknya. Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi kewenangan tidak semata-mata menyangkut pengalihan kewenangan dari atas ke bawah, namun juga perlu diwujudkan atas prakarsa bawah untuk mendorong tumbuhnya kemandirian pemerintahan daerah sebagai faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan ini. Dalam kultur masyarakat Indonesia yang paternalistik, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah tidak akan berhasil apabila tidak didukung oleh upaya sadar untuk membangun keprakarsaan dan kemandirian daerah sendiri.32
Tujuan utama kebijakan desentralisasi adalah untuk membebaskan pemerintah pusat dari berbagai beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik sehingga kesempatan untuk mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaatnya. Pada saat yang sama, pemerintah pusat diharapkan bisa lebih fokus dalam pengambilan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis. Diharapkan dengan adanya desentralisasi ini, daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan. Desentralisasi merupakan simbol kepercayaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, karena dalam sistem otonomi ini pemerintah daerah ditantang secara kreatif untuk menemukan solusi terhadap berbagai masalah yang dihadapi.
31 Martin Jimung, Politik Lokal dan Pemerintah Daerah Dalam Prespektif
Otonomi Daerah (Yogyakarta: Pustaka Nusantama, 2005), 38-39. 32 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta:
Konstitusi Press, 2005), 278.
IDENTITAS SOSIAL DALAM DEMOKRATISASI ... | 89
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Merefleksikan kelemahan pemerintahan pada masa lalu di mana banyak permasalahan daerah yang tidak dapat tertangani secara baik dikareanakan adanya keterbatasan wewenang. Setelah ditetapkannya regulasi yang berkaitan dengan kewenangan pemerintahan daerah, pemerintah dan masyarakat daerah diberikan wewenang untuk mengurus rumah tangga sendiri secara bertanggung jawab. Pada kondisi ini, pemerintah pusat tidak lagi mempatronase apalagi mendominasi.33 Peran pemerintah pada kondisi adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan melakukan evaluasi pelaksanaan otonomi daerah.34 Dalam pelaksanaan otonomi daerah dibutuhkan kombinasi efektif antara visi yang jelas serta kepemimpinan yang kuat dari pemerintah pusat, dengan keleluasaan berprakarsa dan berkreasi pemerintah daerah.
Visi otonomi daerah dapat dirumuskan dalam tiga lingkup interaksi utama, yaitu; politik, ekonomi dan sosial budaya. Pada bidang politik, otonomi daerah harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintah yang dipilih secara demokratis karena otnomi daerah merupakan buah dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi. Pada bidang ekonomi, otonomi daerah harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan otonomi daerah nasional di daerah serta juga membuka peluang bagi pengambilan kebijakan ekonomi regional guna mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Dalam bidang sosial budaya, otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin guna menjaga keseimbangan harmonisasi sosial serta memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang bersifat kondusif terhadap kemampuan masyarakat dalam merespon dinamika kehidupan yang terjadi di sekelilingnya.
Isu otonomi daerah diluncurkan pasca kejatuhan rezim orde baru, seperangkat regulasi yang dijadikan sebagai landasan hukum gerakan otonomi daerah telah diterbitkan. Di antaranya, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada dasarnya, secara historis kebijakan otonomi daerah ini sudah ada sebelum masa reformasi.35 Hal ini dapat dilihat dari beberapa regulasi yang sudah ditetapkan sejak masa kolonialisme.
33 Utang Rosidin, Otonomi Daerah, 49. 34 Ryaas Rasyid, “Otonomi Daerah: Latar Belakang dan Masa Depannya”,
dalam Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi dan
Akuntabilitas Pemerintahan Daerah, ed. Syamsuddin Haris (Jakarta: LIPI Press, 2005), 11.
35 Pemikiran tentang otonomi daerah sudah ada sejak zaman kolonial. Ade Saptomo, Hukum dan Kearifan Lokal, 2. Dalam lieratur lain juga disebutkan bahwa
90 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
1. Masa Kolonialisme Otonomi daerah pada masa kolonial dibentuk semata-mata untuk
menunjang kepentingan politik kolonial, bukan untuk meningkatkan kapasitas politik masyarakat setempat. Sebagian ahli berpendapat bahwa kebijaksanaan penyelenggaraan asas desentralisasi ini didorong oleh komitmen politik etis pemerintah kolonial. Gagasan ini sangat sulit diterima mengingat penyelenggaraan pemerintahan daerah pada masa itu tidak bertujuan untuk memajukan masyarakat, namun cenderung digunakan untuk mempermudah eksploitasi daerah jajahan.36 Hal ini diperkuat dengan sebuah realitas bahwa pada dasarnya sebuah Reglement
op het Beleid der regering van Nederlandsch Indie (Staatsblaad Nomor 1885 Nomor 2) yang ditetapkan guna mengatur pemerintahan kolonial tidak mengenal adanya desentralisasi.37
Hingga tahun 1903, sistem penjajahan di Indonesia dilaksanakan secara monopolistik dan sentralistik. Semua kekuasaan (eksekutif, legislatif dan yudikatif) bertumpu pada seorang Gubernur Jenderal sebagai wakil dari Raja Belanda.38 Pada tahun 1903, pemerintah kolonial
berdasarkan analisis terhadap kondisi sebelum kolonialisasi di Indonesia, adanya praktek pemungutan pajak dan upeti mengindikasikan bahwa pemikiran mengenai otonomi daerah itu sendiri sudah ada, lihat dalam penjelasan M. C. Ricklefs, A History of Modern
Indonesia, 53. Namun sayangnya belum ada penelitian ilmiah tentang terhadap tafsir dan praktek otonomi di nusantara sebelum masa kolonialisasi. B.N. Marbun, Otonomi
Daerah, 27-28. Lihat juga dalam J. Endi Rukmo, “The Role and Function of The Regional People’s Representative Council (DPRD): A Judical Study”, Decentralization
and Regional Autonomy in Indonesia: Implementation and Challenges, eds. Coen J.G. Holtzappel & Martin Ramstedt (Leiden: International Institute for Asian Studies, 2009), 114.
36 Utang Rosidin, Otonomi Daerah, 55. Sebagai sebuah daerah jajahan yang harus menghasilkan keuntungan bagi Kerajaan Belanda, maka ditetapkan bahwa segala urusan pemerintahan penjajahan di Indonesia dipegang oleh seorang Gubernur Jenderal yang berkedudukan di Bogor atau pejabat-pejabat pemerintahan Hindia Belanda yang dikuasai oleh Guberbur Jenderal. C.S.T. Kansil, Hukum Tata Pemerintahan, 246
37 Josef Riwo Kaho, Prospek Otonomi Daerah, 23. Lihat juga dalam Syaukani, et. all., Otonomi Daerah, 50. Lihat juga dalam Martin Jimung, Politik Lokal, 130-132.
38 Pedoman yang dipakai sebagai landasan pemerintahan pada masa ini adalah Regerings Reglement (RR) yang dibuat di negeri Belanda pada tahun 1854. Sampai tahun 1903, tidak ditemukan satu ketentuan pasal pun dalam RR yang mengatur perihal otonomi daerah ataupun prinsip dasar desentralisasi. Hanya saja, RR mempunyai bahasan yang berkaitan dengan sistem kepemimpinan. Hal ini dinyatakan dalam pasal 67 RR, yaitu: “sepanjang keadaan mengizinkan, maka rakyat Bumiputera dibiarkan berada di bawah pimpinan langsung kepala-kepalanya baik yang diangkat pemerintah ataupun yang diakui, berada di bawah pengawasan sesuai dengan ketentuan-ketentuan umum atau khusus yang telah ditetapkan atau yang akan ditetapkan oleh Gubernur Jenderal”. Penjelasan lebih lanjut lihat B.N. Marbun, Otonomi Daerah, 28-29.
IDENTITAS SOSIAL DALAM DEMOKRATISASI ... | 91
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
menetapkan Staatsblaad Nomor 329 Tahun 1903 atau yang lebih dikenal dengan istilah decentralisatiewet
39 yang memberikan peluang untuk terbentuknya gewest (satuan pemerintahan) yang mempunyai kekuasaan finansial tersendiri.40 Pemerintahan diserahkan kepada raad (dewan) yang berada di masing-masing wilayah. Sebelum berlakunya regulasi ini, metode pemerintahan kolonial Belanda mendapat kritikan tajam dari para tokoh intelektual dan partai oposisi di Belanda.41 Para tokoh intelektual dan partai oposisi di Belanda menghendaki diberlakukannya etische
politiek (politik etis)42 atas daerah jajahan, termasuk Indonesia. Regulasi ini kemudian diperkuat oleh penetapan Staatsblaad
Nomor 137 Tahun 1905 (descentralisatiebesluit) dan Staatsblaad Nomor 181 Tahun 1905 (locale radenordanntie). Regulasi ini kemudian memprakarsai terbentuknya local resort dan local raad. Meskipun demikian, pemerintahan daerah pada masa ini tidak mempunyai kewenangan yang memadai, hal ini dikarenakan sebagian keanggotaan raad diangkat dari pegawai pemerintahan. Locale raad (Dewan Daerah) berhak membentuk locale verordeningen (peraturan setempat) menyangkut berbagai hal yang belum diatur secara spesifik oleh pemerintah kolonial. Pengawasan terhadap pemerintahan setempat
39 Pada tanggal 23 Juli 1903, regulasi tentang desentralisasi di daerah Hindia
Belanda yang bernama de Wet Houdende Decentralisatie van Het Berstuur in
Netherlands Indie berhasil diterima sidang dan diundangkan dalam Staatsblaad van Het
Koninkirjk der Nederlanden Tahun 1903 Nomor 219. Undang-undang tersebut kemudian juga diundangkan di Hindia Belanda melalui Indische Staatsblaad Nomor 329 dan dikenal dengan istilah Desentralisatie Wet 1903. Pada dasarnya, regulasi ini merupakan penambahan 3 ayat baru terhadap pada pasal 68 Regerings Reglement. B.N. Marbun, Otonomi Daerah, 30-31.
40 Josef Riwo Kaho, Prospek Otonomi Daerah, 24. 41 Susunan pemerintahan Hindia Belanda yang sentralistik berlangsung hingga
permulaan abad ke-XX. Hal ini menimbulkan reaksi dari Negara-negara Eropa, Timur Asing, dan dari kalangan intelektual Indonesia sendiri. Martin Jimung, Politik Lokal, 131.
42 Ada beberapa tokoh yang berjuang dalam memperbaiki sistem pemerintahan di daerah jajahan, seperti; T.A.J. van Asch van Wijck dan A.M.F. Idenburg yang juga merupakan Menteri Daerah Jajahan pada masa itu. Sementara itu, Van Deventer dikenal sebagai seorang pelopor kemunculan etische politiek dengan memberikan masukan kepada pihak Hindia Belanda untuk meringankan beban pajak dan memberikan kesejahteraan dalam bidang pendidikan. Kelahiran Decentralisatie Wet 1903 ini merupakan hasil perjuangan pelopor perubahan sistem pemerintahan Hindia Belanda selama kurnag lebih 50 tahun. Penjelasan lebih lanjut lihat dalam Soetandyo Wignyosoebroto, Desentralisasi Dalam Tata Pemerintahan Hindia Belanda (Malang: Bayu media, 2004), 10-19.
92 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
dilakukan langsung oleh gouverneur-generaal (Gubernur Jenderal) Hindia Belanda yang berkedudukan di Batavia.
Bertitik tolak dari praktik dan sejarah, dapat disimpulkan bahwa implementasi desentralisasi pada masa tersebut tidak berjalan dengan baik dan bahkan mendapat banyak kritikan baik dari kalangan tokoh Belanda sendiri ataupun dari kalangan intelektual Indonesia. Hal ini terlihat dengan munculnya pergerakan yang berskala nasional di Indonesia pada tanggal 20 Mei 1908, bahkan peristiwa tersbut diabadikan sebagai salah satu hari libur nasional. Pergerakan nasional ini pada dasarnya merupakan desakan kepada pemerintah kolonial untuk memberikan status dominion kepada wilayah-wilayah Hindia Belanda.43 Pergerakan ini menandakan adanya ketidakpuasan dam kegagalan desentralisasi dalam memberikan hak otonomi kepada berbagai daerah pada masa itu.
Kebijakan desentralisasi ini masih belanjut hingga pada tahun 1922 pemerintah kolonial menetapkan Staatsblaad Nomor 216 Tahun 1922 (wet op de Bestuurshervormin). Regulasi ini menegaskan pembagian daerah dan pembentukan provincie, regentschap, stadsgemeente dan groepmeneeschap. Pembentukan daerah-daerah baru ini menggantikan locale resort yang sudah dibentuk berdasarkan regulasi sebelumnya. Pembentukan sejumlah daerah diikuti dengan ditetapkannya ordantie, seperti; ordantie pembentukan Provincie Jawa Madura, Provincie West Java, Regentschap Batavia. Sedangkan untuk pulau-pulau yang berada di luar Jawa dan Madura dibentuk atas Groepsmeenschaps
Ordantie. Selain daerah-daerah dengan sistem pemerintahan baru tersebut,
terdapat juga beberapa daerah pemerintahan yang merupakan bentuk persekutuan asli masyarakat setempat atau yang dikenal juga dengan istilah zelfbestuurende landschappen.44 Di samping itu, juga ada bentuk
43 Dominion merupakan bentuk kebijakan dengan memberikan ruang gerak bagi
daerah jajahan untuk mengurus kepentingan rumah tangganyan sendiri, seperti yang dilakukan oleh penjajah Inggris terhadap daerah-daerah jajahannya. Dalam konteks Indonesia, tuntutan ini terlihat dengan adanya desakan untuk membentuk satu Dewan Perwakilan Rayat Pusat yang diberikan kekuasaan dan kewenangan dalam menetapkan regulasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Soehino, Perkembangan Pemerintahan di
Daerah (Yogyakarta: Liberty, 1980), 7. 44 Josef Riwo Kaho, Prospek Otonomi Daerah, 27. Zelfbestuurende
landschappen merupakan persekutuan masyarakat adat yang tetap diakui keberadaanya pada masa kolonialisasi Belanda. Wujudnya adalah bentuk desa di pulau Jawa dan bentuk nagari di Minangkabau. Desa di Jawa kemudian diatur lebih lanjut dalam Inlandsche Gemmeente Ordantie (Staatsblaad Nomor 83 Tahun 1906) dan untuk masyarakat adat di luar pulau Jawa ditur dalam Inlandsche Gemmeente Ordantie
Buitengewesten (Staatsblaad Nomor 507 Tahun 1931). The Liang Gie, Pertumbuhan
IDENTITAS SOSIAL DALAM DEMOKRATISASI ... | 93
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
pemerintahan kerajaan yang sudah ada jauh sebelum kedatangan Belanda ke Indonesia. Terhadap kerajaan-kerajaan ini, Belanda mengadakan perjanjian dan kontrak politik untuk mengikatnya. Kontrak politik yang diajukan oleh Belanda ini terbagi dalam 2 bentuk, yaitu lange contracten (kontrak jangka panjang) dan korte verklaring (kontrak jangka pendek). Dalam lange verklaring, kekuasaan pemerintah kolonial disebutkan secara rinci sedangkan untuk kewenangan di luar yang disebutkan dalam kontrak akan tetap berada dalam kewenangan kerajaan. Sementara dalam korte verklaring terdapat pengakuan secara penuh terhadap kekuasaan kolonial dan berjanji untuk tunduk dan mengikut semua aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah kolonial.
Kondisi ini mengantarkan masyarakat pada dualisme administrasi pemerintahan.45 Di satu sisi, masyarakat dihadapkan dengan pemerintahan yang jalankan oleh kolonial. Sementara itu di sisi lain, rakyat juga berhadapan dengan administrasi pemerintahan asli yang dijalankan oleh pihak kerajaan. Terlepas dari hal tersebut, kondisi utama yang harus dicermati adalah adanya kecenderungan sentralisasi pemerintahan dan pola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertingkat. Sampai masa ini, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa bentuk pemerintahan otonomi daerah sudah ada di Hindia Belanda sejak tahun 1903. Titik berat otonomi tersebut ditempuh dengan jalan dekonsentrasi dan desentralisasi serta tugas medebewind (pembantuan).46 Pada masa ini juga telah dikenal berbagai daerah swapraja dan desa sebagai implementasi bentuk daerah otonom berdasarkan hukum adat.
Pada masa kekuasaan Belanda di Indonesia, terjadi Perang Dunia ke-2 dan efeknya terasa sampai ke Asia Timur. Jepang pada waktu itu mempunyai kekuatan militer yang sangat kuat dan melakukan invansi ke Asia Timur, mulai dari Korea Utara hingga pulau Jawa dan Sumatera. Bermodalkan kekuatan militer ini juga, Jepang berhasil menaklukkan kekuatan Inggris di berbagai wilayah dan kekuatan Belanda di Hindia Belanda. Kolonialisasi Jepang di Indonesia yang bisa dikatakan singkat, hanya 3,5 tahun (1941-1945) ternyata mampu memberikan perubahan yang fundamental terhadap penyelenggaraan kekuasaan di daerah Hindia Belanda.
Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 1993), jilid 1, ed-2, 19. Lihat juga dalam Soehino, Perkembangan Pemerintahan, 5-6. Dalam beberapa literatur lain, persekutuan masyarakat hukum adat ini juga dikenal dengan term inlandse rechtsgemeenschappen. B.N. Marbun, Otonomi Daerah, 29.
45 Utang Rosidin, Otonomi Daerah, 57. 46 Soehino, Perkembangan Pemerintahan, 12-13.
94 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Jepang yang menggantikan penjajahan Belanda pada awalnya menjanjikan perubahan sistem pemerintahan kolonial, namun pada akhirnya masih meneruskan sistem dekonsentrasi dan sentralistik dengan mengadakan perubahan-perubahan kecil, seperti penamaan daerah dan jabatan yang menggunakan bahasa Jepang. Hindia Belanda dibagi menjadi tiga wilayah utama oleh otoritas pemerintahan kolonial Jepang, masing-masing wilayah berada dalam kekuasaan militer. Sumatera dengan pusat pemerintahan di Kota Bukit Tinggi berada di bawah kekuasaan militer Angkatan Darat, Pulau Jawa dan Madura dengan pusat pemerintahan di Jakarta beserta wilayah timur seperti Sulawesi, Kalimantan, Sunda Kecil dan Maluku berada dalam kewenangan militer Angkatan Laut.
Pada masa penguasaan Jepang di Hindia Belanda, pihak militer Jepang (gunsireikan) menetapkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1942 atau yang sering dikenal dengan osamu sierei berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan regulasi tersebut, wilayah Jawa dibagi menjadi beberapa bagian.47 Untuk pertama kalinya, pada masa ini provincie tidak masuk dalam bentuk strata pemerintahan di Jawa. Jabatan-jabatan yang dahulunya diduduki oleh orang Belanda digantikan oleh pejabat-pejabat Jepang. Hal ini menunjukkan bahwa asas desentralisasi yang awalnya mulai dibangun oleh kolonial Belanda kemudian dihapus dan dicabut eksistensinya.
Tidak jauh berbeda dengan masa kolonialisasi yang dilakukan oleh Belanda, pada masa kolonialisasi Jepang pemerintahan daerah juga tidak mempunyai keleluasaan dalam menggunakan wewenangnya.48 Penggunaan term daerah otonom bagi pemerintahan daerah pada masa ini merupakan sesuatu hal yang bersifat misleading atau menyesatkan.49 Bahkan, dalam kenyataannya administrasi pemerintah militer Jepang melakukan penetrasi secara dominan dan intensif apabila dibandingkan dengan masa kolonialisasi Belanda. Hal ini dikarenakan meningkat dan
47 Merujuk pada osami sierei, wilayah Jawah dibagi dalam beberapa syuu yang dipimpin oleh syuutyokan. Syuu dibagi kepada beberapa ken yang dipimpin oleh kentyoo. Ken juga dibagi menjadi beberapa si yang dimpimpin oleh sityoo. Daerah yang berkedudukan khusus disebut dengan tokubetu si yang mempunyai kedudukan setingkat syuu dan dipimpin oleh seorang tokubetu sityoo. Pemerintahan Jepang juga menghapus raad yang sudah dibentuk oleh Belanda pada masa sebelumnya. The Liang Gie, Pertumbuhan Pemerintahan, 21.
48 Berbagai kebijakan dan keputusan yang dibuat pada masa penjajahan Jepang bersifat sentralistik dan militeristik. Tujuan utamanya adalah memenuhi kebutuhan pemerintah jepang itu sendiri sehingga fungsi-fungsi pemerintahan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Martin Jimung, Politik Lokal, 143.
49 Utang Rosidin, Otonomi Daerah, 59.
IDENTITAS SOSIAL DALAM DEMOKRATISASI ... | 95
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
mendesaknya kebutuhan mobiliasi sosial guna mendukung Jepang dalam peperangannya, sementara personil Jepang sendiri tidak memadai untuk melakukannya sendiri. Hal ini menuntut pemerintah jepang untuk tergantung pada para pangreh praja dalam rangka mobilisasi dukungan dalam peperangan. Para pangreh praja tersebut memiliki kekuasaan yang sangat besar, namun masih berada di bawah penguasaan penuh pihak militer Jepang.
2. Era Demokrasi Perlementer
Uraian mengenai perkembangan otonomi daerah dan penerapan asas desentralisasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan sangat bervariasi sesuai dengan konteks yang dikaji dalam undang-undangnya. Hal utama yang menjadi catatan penting adalah bahwa pembentukan, pertumbuhan dan pergeseran kedudukan otonomi daerah selalu dikaitkan dengan ketentuan Undang-undang Dasar dan produk perundang-undangan yang mengatur pemerintahan daerah.
Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan Undang-undang Dasar 1945. PPKI kemudian juga membentuk Panitia Kecil yang ditugaskan untuk mengurus hal-hal yang harus diselesaikan segera. Hal-hal tersebut mencakup 4 masalah pokok, yaitu; urusan rakyat, pemerintahan daerah, pimpinan kepolisian dan tentara kebangsaan.50 Dengan diusulkannya masalah pemerintah daerah sebagai salah satu masalah penting yang hrus diseselsaikan dan juga dengan memperhatikan pasal 18 UUD 1945. Ketentuan pasal ini jelas sekali mengindikasikan kuatnya political will pada pendiri negara untuk memberikan tempat terhormat dan penting bagi daerah-daerah dalam sistem politik nasional.
Regulasi otonomi daerah yang pertama kali ditetapkan pada masa demokrasi parlementer tahun 1945. Berdasarkan Maklumat X tanggal 16 Oktober 1945 dan berakhir dengan adanya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Pada era parlementer ini, berdasarkan Maklumat X, Indonesia menyelenggarakan sistem pemerintahan parlementer51 dengan adanya Perdana Menteri yang melaksanakan kebijakan politik berdasarkan perimbangan kekuatan partai di DPR. Presiden hanya sebagai kepala Negara dan bukan kepala pemerintahan.
Titik awal kajian mengenai desentralisasi dan otonomi daerah pada era kemerdekaan selalu dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 1
50 Josef Riwo Kaho, Prospek Otonomi Daerah, 30. Lihat juga Martin Jimung,
Politik Lokal, 153. 51 B.N. Marbun, Otonomi Daerah, 47-48.
96 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Tahun 1945. Pada tanggal 30 Oktober 1945, Badan Pekerja Komite Nasional Pusat mengeluarkan pengumuman Nomor 2 mengenai rancangan Undang-undang tentang kedudukan Komite Nasional Daerah. Dalam pengumuman ini dinyatakan bahwa BP KNIP telah menyerahkan Rancangan Undang-undang kepada presiden guna mengatur kedudukan Komite Nasional Daerah yang disesuaikan dengan perkembangan KNIP. RUU tersebut disetujui oleh pemerintah pada tanggal 23 November 1945 dan ditetapkan menjadi Undaug-undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Komite Nasional Daerah.
Berdasarkan undang-undang ini, kebijakan otonomi daerah lebih menitikberatkan pada asas dekonsentrasi. Kepala daerah hanyalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Otonomi yang diberikan kepada daerah-daerah Republik Indonesia lebih luas daripada otonomi era Hindia Belanda. Berdasarkan regulasi ini juga dapat disimpulkan bahwa lembaga legislatif daerah juga merangkap menjadi bagian dari lembaga eksekutif daerah.
Merujuk pada regulasi ini,52 daerah-daerah di Indonesia dibagi menjadi dua bentuk, yaitu daerah otonom dan daerah istimewa. Masing-masingnya dibagi dalam tiga tingkatan daerah, yaitu; provinsi, kabupaten/kota besar dan desa/kota kecil. Dalam perjalanannya, Komite Nasional Daerah (KND) berubah menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah (BPRD) yang dipimpin oleh kepala daerah.53 BPRD bertugas menjalankan dan mengatur urusan rumah tangga daerah dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang lebih luas. Jumlah anggota BPRD untuk keredisenan adalah 100 orang dan 60 orang untuk tingkat kabupaten/kota.
Setelah regulasi ini ditetapkan, perlahan-lahan KND di Jawa dan Madura diseuaikan kedudukannya menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam regulasi tersebut. Di Jawa dan Madura terdapat 17 daerah karesidenan. Pada saat berlaku aturan ini, di Jawa terdapat 18 daerah
52 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 ditetapkan tanggal 23 November 1945.
Regulasi ini mengatur pembentukan Komite Nasional Daerah (KND) pada tingkat keresidenan, kabupaten, kota berotonomi dan daerah-daerah lain yang dianggap perlu selain Yogyakarta dan Surakarta. Regulasi ini juga mengatur kedudukan dan kekuasaan KND sehingga dapat dianggap sebagai regulasi yang mengatur desentralisasi pertama kali. Utang Rosidin, Otonomi Daerah, 61. Pola pembagian daerah dalam regulasi ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 Undang-undang Dasar 1945.
53 Dalam regulasi ini tidak dijelaskan secara rinci siapa kepala daerah yang dimaksud. Akan tetapi, dalam praktik di lapangan kepala daerah adalah kepala pemerintahan pamong praja yang ada pada tingkat daerah yang bersangkutan.
IDENTITAS SOSIAL DALAM DEMOKRATISASI ... | 97
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
otonom serta warisan masa lampau di Jawa terdapat 67 daerah otonom.54 Bersamaan dengan adanya perubahan KND menjadi BPRD, umumnya KND yang sudah ada pada beberapa daerah tetap dilanjutkan. Namun juga ada beberapa daerah tertentu yang membetuk KND baru, atau menambah keanggotaan yang masih dirasa kurang. Sementara itu, tata cara penyusunan badan-badan tersebut diserahkan kepada daerah masing-masing.
Perubahan peranan KND menjadi badan legislatif dengan nama BPRD maka badan tersebut pada dasarnya hanya bertugas untuk membuat peraturan-peraturan pada tingkat daerah.55 Pada umumnya, hal-hal yang diatur oleh BPRD adalah penerusan wewenang suatu daerah yang diwarisi dari masa Hindia Belanda dan pendudukan Jepang. Selain itu, sehubungan dengan adanya upaya Belanda untuk ingin kembali menguasai Indonesia, maka daerah-daerah mengatur pula urusan-urusan yang berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban.
Jika dibandingkan dengan konteks Indonesia modern, BPRD mempunyai wewenang yang tidak jauh berbeda dengan wewenang Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) sekarang. Di antara kewenangan yang dimaksud adalah sebagai berikut.
a. membuat peraturan-peraturan yang dibutuhkan untuk kepentingan daerahnya;
b. membantu menjalankan peraturan-peraturan dari pemerintahan yang lebih tinggi (medebewind dan selfgovernment), dan;
c. membuat peraturan pelaksana undang-undang dengan pengesahan oleh pemerintah atasan.
Dalam pelaksanaan tugas mengatur dan mengurus ini belum ada
batasan yang jelas antara pelaksanaan otonomi dengan tugas kepada daerah dalam rangka dekonsentrasi. Demikian juga halnya dengan hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah. Meskipun regulasi ini merupakan regulasi pertama yang mengatur perihal pemerintahan daerah, namun tidak pernah menyebutkan pemerintahan daerah, melainkan Komite Nasional Daerah (KND). Hal ini sangat jauh berbeda dengan
54 B.N. Marbun, Otonomi Daerah, 47-52-53. 55 Di Kota Jakarta misalnya, surat-surat izin cukup hanya dikeluarkan oleh
jawatan-jawatan pemerintah kota. Dalam menetapkan peraturan daerah, BPRD dari berbagai daerah menggunakan beragam istilah yang berbeda, seperti; maklumat, peraturan atau aturan. Hal dapat dimaklumi mengingat pada masa itu belum ada keseragaman bentuk dan nama bagi peraturan yang dikeluarkan. The Liang Gie, Kumpulan Pembahasan Terhadap Undang-undang Tentang Pokok-pokok Pemerintahan
Daerah di Indonesia (Yogyakarta: Kencana, 1977), 37.
98 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
regulasi yang muncul setelahnya yang secara tegas menyebutkan pemerintahan daerah.
Secara eksplisit, regulasi ini menyebutkan bahwa pada tingkat kedewanan atau yang lebih rendah, tidak diadakan KND. Demikian juga halnya dengan tingkat provinsi yang juga meniadakan KND. Hal disebabkan karena provinsi telah dihapuskan ketika masa pendudukan Jepang. Sementara itu, provinsi yang dibentuk pada 19 Agustus 1945 hanya bersifat administratif.56 Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa pada tingkat provinsi, kewedanan dan kecamatan tidak berkedudukan sebagai daerah otonom dikarenakan tidak mempunyai KND sehingga daerah tersebut hanya merupakan unsur dekonsentarasi yang menjalankan pemerintahan umum di daerahnya.
Ketidakjelasan batasan-batasan dalam urusan rumah tangga dalam regulasi ini berakibat pada ketidaktahuan pemerintah daerah denga urusan rumah tangga daerah secara rinci dan efektif.57 Adanya ketidakjelasan ini didorong oleh kurangnya inisiatif daerah serta keterbatasan pengalaman semakin menyempitkan pelaksanaan regulasi ini. Hal ini juga diperparah dengan kondisi sosial politik tahun 1945 dalam suasana revolusi menghadapi upaya Belanda untuk menguasai Indonesia kembali.
Apabila dilakukan evaluasi secara menyeluruh pada regulasi ini, dapat disimpulkan bahwa regulasi ini merupakan terobosan baru meskipun pada beberapa bagiannya masih dapat dikatakan jauh dari sempurna, terutama bentuk otonomi yang hendak diterapkan yang masih belum terincikan. Hal ini dapat dimaklumi karena pada masa ini belum ada rumusan baku terkait otonomi yang hendak diterapkan sebagai otonomi Indonesia yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat.
Eksistensi regulasi ini dinilai belum mampu menjadi landasan yang menyeluruh dan terperinci dalam pengaturan pemerintahan daerah dan tata cara penyelenggaraannya. Hal ini yang mendorong untuk ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah yang diundangkan pada tanggal 10 Juli 1948. Regulasi baru ini menganut sistem otonomi formal,58 karena
56 B.N. Marbun, Otonomi Daerah, 47-54. 57 The Liang Gie, Kumpulan Pembahasan, 34. 58 Menurut Koentjoro, otonomi formal merupakan pelimpahan atau penyerahan
wewenang yang dalam undang-undang ditetapkan dan dirincikan secara tegas dari pemerintah pusat, atas dasar satu pola yang sama bagi setiap daerah swatantra namun tidak dilengkapi dengan sumber keuangan yang nyata dan perlengkapan. Pemerintah daerah yang mampu mengerjakan tugasnya dalam praktiknya ternyata menimbulkan kekecewaan dan ketidakpuasan dari daerah yang bersangkutan. Utang Rosidin, Otonomi
Daerah, 63.
IDENTITAS SOSIAL DALAM DEMOKRATISASI ... | 99
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
tidak melihat keadaan masyarakat daerahnya. Sejak ditetapkannya regulasi ini, kebijakan otonomi daerah lebih menitikberatkan pada asas desentralisasi. Namun, pada masa ini kepala daerah masih mempunyai peran ganda (dualisme) dalam jabatannya selaku alat pemerintah pusat yang berkedudukan di daerah dan sebagai orang yang paling berperan dalam mengurus rumah tangga daerahnya.
Berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam regulasi ini, daerah Republik Indonesia dibagi dalam tiga tingkatan daerah yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri, yaitu;
a. daerah tingkat I (satu) yang dikenal dengan provinsi; b. daerah tingkat II (dua) yang dikenal dengan kabupaten/kota besar,
dan; c. daerah tingkat III (tiga) yang dikenal dengan desa (juga termasuk
di dalamnya nagari, marga dan lain sebagainya) dan kota kecil.
Hal menarik dalam regulasi ini adalah adanya restorasi kedudukan provinsi seperti pada masa Hindia Belanda, bahkan tidak hanya diakui sebagai daerah administratif belaka, namun juga diberikan kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Sementara itu, bentuk keresidenan dihapuskan dan berdasarkan ketentuannya akan dibentuk pemerintahan desa dan kota kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa jika pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 lebih menekankan pada ide kedaulatan rakyat, maka pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 penekanan ditujukan pada pemerintahan daerah yang demokratis.59
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 menentukan bahwa pemerintah daerah terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Pemerintahan Daerah (DPD). Jabatan kepala daerah atau yang disingkat dengan KDH sebagai wakil pemerintah pusat yang berada di daerah, berkedudukan sebagai Ketua sekaligus merangkap Anggota DPD. Pengangkatannya dipilih dari calon yang diajukan oleh DPRD. DPRD juga mempunyai wewenang untuk memberikan usulan pemberhentian kepala daerah kepada pemerintah pusat. Sehingga terlihat bahwa eksistensi undang-undang ini mengharuskan adanya hubungan kolegial dalam menjalankan pemerintahan.
59 Apabila dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 yang
lebih mengedepankan konsep gagasan kedaulatan rakyat, maka Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 lebih memberikan penekanan pada pemerintahan yang demokratis. Hal ini terlihat sangat jelas dalam ketentuan-ketentuan beserta penjelasan yang dimuat di dalamnya. B.N. Marbun, Otonomi Daerah, 55. Bandingkan dengan Utang Rosidin, Otonomi Daerah, 63.
100 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Terkait masalah kekuasaan pemerintah daerah, regulasi ini menjelaskan batasan dan kewenangan yang rinci. Regulasi ini menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah didasarkan pada hak otonomi dan hak medebewind. Hak otonomi adalah hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Medebewind merupakan hak untuk menjalankan peraturan dari pemerintah pusat atau dari daerah yang tingkatnya lebih tinggi berdasarkan perintah atasan tersebut.
Implementasi regulasi ini juga tidak berjalan mulus seperti regulasi sebelumnya. Hal ini dikarenakan regulasi ini hanya diterapkan untuk Pulau Sumatera. Pada 14 April 1948 juga ditetapkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1948 tentang Pembagian Sumatera menjadi 3 provinsi, yaitu; Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1948 juga dibentuk Komisariat Pemerintah Pusat. Meskipun daerah tersebut mempunyai Anggota DPRD, namun dalam praktiknya mereka merupakan anggota DPR Sumatera yang berasal dari sub-provinsi semula.
Upaya penerapan asas desentralisasi di Sumatera juga sempat terhenti karena adanya Agresi Militer II Belanda pada Desember 1948. Hal ini berdampak pada bedirinya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera dan beberapa wilayah lain yang dibina oleh penguasa militer, gubernur-gubernur dan komisariat pemerintah pusat. Pelaksanaan regulasi ini secara efektif dimulai ketika akan dibentuknya NKRI. Hal ini ditandai dengan mulai dibentuknya provinsi, kabupaten, kota besar dan kecil di jawa dan Sumatera. Sementara itu, di Indonesia bagian timur berlaku regulasi desentralisasi yang diciptakan oleh Hindia Belanda.
Faktor eksternal yang mempengaruhi pengesahan Undang-undang ini adalah adanya perang kemerdekaan yang disusul dengan adanya hasil Konfrensi Meja Bundar60 yang menyatakan pembentukan Republik
60 Kondisi ini berakibat pada kegagalan penerapan regulasi tersebut secara
menyeluruh. Dengan berdasarkan berbagai regulasi pembentukan, maka dibentuklah beberapa daerah otonom di Jawa, Madura dan Sumatera pada tahun 1950 dan Kalimantan pada tahun 1953. Bagi wilayah Negara Indonesia Timur, diberlakukan Staatsblaad Indonesia Timur (SIT) Nomor 44 Tahun 1950. Pada dasarnya, isi dan jiwa SIT Nomor 44 Tahun 1950 ini hampir sama dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 yang disesuaikan dengan struktur negara bagian. Josef Riwo Kaho, Prospek
Otonomi Daerah, 35-37. Kebijakan ini bersifat sementara. Hal ini terlihat dari Konsideran SIT yang menyebutkan bahwa apabila sewaktu-waktu terjadi penggabungan kembali menjadi negara yang yang berbentuk kesatuan, maka akan kembali pada Undang-undang Nonor 22 tahun 1948. Martin Jimung, Politik Lokal, 166.
IDENTITAS SOSIAL DALAM DEMOKRATISASI ... | 101
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Indonesia Serikat (RIS) dengan pemberlakuan Konstitusi RIS. Tidak sampai setahun kemudian, Konstitusi RIS dirubah lagi menjadi Undang-undang Dasar Sementara 1950 yang mulai berlaku sejak 15 Agustus 1950. Pada masa ini, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan Undang-undang yang cukup liberal dan penuh kompromi.
Adanya semangat kedaerahan yang cukup liberal berakibat pada banyaknya suara-suara di Parlemen dan Daerah yang menuntut adanya upaya peninjauan dan penyesuaian regulasi dengan keadaan pada saat itu.61 Keberagaman regulasi yang mengatur desentralisasi menuntut diadakanya penyeragaman peraturan yang berlaku dalam skala nasional. Guna menghadapi tuntutan ini, pemerintah telah berupaya melakukan berbagai perubahan yang dianggap perlu dalam menyesuaikan dengan semakin berkembangnya Indonesia. Namun, upaya tersebut mengalami kegagalan dan berujung dengan kemunculan ide untuk mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan di daerah oleh pemerintah pusat. Hal inilah yang kemudian menjadi latar belakang ditetapkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957.
Term daerah otonom, sebagaimana yang dikenal pada masa berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 diganti dengan istilah swatantra dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957. Merujuk pada ketentuan yang dimuat dalam regulasi ini, wilayah Republik Indonesia dibagi menjadi daerah besar dan daerah kecil yang diberikan hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam tiga tingkatan, berikut;
a. daerah swatantra tingkat I, termasuk kotapraja dan Jakarta Raya; b. daerah swatantra tingkat II, dan; c. daerah swatantra tingkat III.
Berdasarkan regulasi ini, maka semua daerah otonom yang sudah
dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 mengalam konversi perubahan nama. Provinsi yang sudah dibentuk sebelumnya diganti menjadi daerah swatantra tingkat I dan kabupaten berubah menjadi daerah swatantra tingkat II. Sementara itu, kota besar dan kota kecil yang sudah dibentuk menjadi kota praja setingkat dengan daerah swatantra tingkat II, kecuali Kota Praja Jakarta Raya yang setingkat dengan daerah swatantra tingkat I.
Hal yang baru dibentuk dalam regulasi ini adalah mulai adanya fungsi pengawasan. Pengawasan pemerintah pusat terhadap dilakukan dengan sangat ketat dalam dua bentuk, sebagai berikut.
61 B.N. Marbun, Otonomi Daerah, 62-63.
102 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
a. pengawasan preventif dilakukan terhadap beberapa keputusan tertentu yang menyangkut kepentingan-kepentingan besar atau mungkin akan memicu kegelisahan dan gangguan-gangguan terkait kepentingan umum oleh pemerintah daerah, sehingga diharapkan dapat dilakukan upaya pencegahan terlebih dahulu terhadap kemungkinan kerusakan dan kerugian tersebut;
b. pengawasan represif berupa pambatalan atau penangguhan keputusan daerah yang telah dikeluarkan dan bertentangan dengan kepentingan umum, undang-undang, peraturan pemerintah atau peraturan lain yang lebih tinggi tingkatannya.
Pada saat undang-undang ini diberlakukan, pemerintah daerah
sudah benar-benar demokratis. Hal ini mengandung pengertian bahwa keanggotaan DPRD dipilih oleh rakyat, keanggotaan DPD dipilih oleh DPRD, kepala daerah dipilih oleh DPRD, DPRD mengangkat sekretaris daerah serta DPD bertanggung jawab kepada DPRD. Proses pembentukan undang-undang ini dilatarbelakangi oleh konfigurasi politik yang sangat demokratis sehingga memunculkan produk hukum yang responsif dan populistik.62 Undang-undang ini berlaku di bawah UUDS 1950 sehingga menitikberatkan pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat (1) UUDS 1950. Daerah-daerah di luar pulau Jawa merasa puas dengan implementasi undang-undang ini.
Berbeda dengan konsep otonomi formal yang diusung dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 ini menganut sistem otonomi real.63 Dalam penjelasan Undang-undang ini disebutkan bahwa sistem otonomi real64 dinyatakan sebagai suatu sistem ketatanegaraan dalam lapangan penyelenggaraan
62 Moh. Mahfud M.D., Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: LP3ES, 1998),
333. 63 Pernyataan ini disampaikan oleh Mr. Kuntjoro Purbopranoto yang pada
waktu itu menjabat kepala bagian Otonomi dan Desentralisasi pada Kementerian dalam Negeri. Penjelasan lebih lanjut dapat ditemukan dalam The Liang Gie, Kumpulan
Pembahasan, 69. Lihat juga dalam B.N. Marbun, Otonomi Daerah, 65. Utang Rosidin, Otonomi Daerah, 59.
64 Undang-undang ini adalah undang-undang yang pertama memperkenalkan konsep otonomi real yang kemudian diikuti oleh undang-undang tentang pemerintahan daerah beserta berbagai variasinya. Dasar pemikiran dalam konsep ini adalah kenyataan kehidupan masyarakat yang penuh dengan dinamika dan pertumbuhan. The Liang Gie, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah, 114. Hal yang sama juga dijelaskan lebih lanjut dalam J. Wajong, Asas-asas dan Tujuan Pemerintahan Daerah (Jakarta: Djambatan, 1975). Keterangan lebih lanjut dapat ditemukan dalam Josef Riwo Kaho, Prospek
Otonomi Daerah, 40-41.
IDENTITAS SOSIAL DALAM DEMOKRATISASI ... | 103
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
desentraliasi yang berdasarkan pada keadaan dan faktor-faktor yang nyata, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang nyata didaerah manapun. Sistem otonomi riil yang dimaksud di sini adalah tidak adanya perincian dalam dalam pembentukan daerah otonom, namun daerah otonom diberikan kekuasaan dan kewenangan secara luas. Pengurusan rumah tangga sendiri diserahkan kepada pemerintah daerah. Sementara pemerintah pusat hanya mempunyai wewenang dalam hal-hal yang menurut undang-undang ditetapkan sebagai kewenangan pemerintah pusat.
Konsekuensi logis sebagai sebuah negara kesatuan, maka rumusan otonomi yang seluas-luasnya pada hakikatnya tidak boleh mengakibatkan kerusakan hubungan negara dengan daerah, demikian juga dengan hubungan antardaerah. Untuk menjamin keselarasan ini, maka pemerintah pusat mempunyai hak untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan daerah yang mungkin akan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan juga terhadap tindakan-tindakan yang akan mengganggu kedudukan negara sebagai satu kebulatan yang harmonis.
Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Undang-undang ini cukup menarik dan merupakan batu landasan utama dalam upaya pembentukan regulasi yang mengatur masalah desentraliasi yang cukup luas. Meskipun demikian, semakin berkembangnya zaman dan masyarakat, dibutuhkan sebuah peraturan yang mengatur secara lebih spesifik dan efisien. Berlarutnya pembahasan mengenai Konstitusi Republik Indonesia yang baru di Konstituante mengakibatkan Presiden Soekarno mengumumkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, yang berisikan pernyataan bahwa Indonesia kembali pada Undang-undang Dasar 1945 dan menyatakan bahwa Undang-undang Dasar 1945 adalah konstritusi resmi Republik Indonesia. Perubahan konstitusi ini membawa pengaruh yang luas dalam bidang ketata-negaraan Republik Indonesia. Beberapa produk hukum yang berlandaskan pada UUDS 1950 harus disesuaikan dengan jiwa UUD 1945. Kembali konstitusi ke bentuk UUD 1945, barakibat pada kembalinya kedudukan pemerintah sebagai posisi sentral. Tuntutan otonomi yang seluas-luasnya bergeser ke arah demokrasi terpimpin yang sesuai dengan iklim perpolitikan pada masa itu.
3. Era Demokrasi Terpimpin
Untuk menyesuaikan kondisi perpolitikan dengan kondisi ketatanegaraan Indonesia pada masa itu, Presiden menetapkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 pada tanggal 7 November 1959. Peraturan presiden ini kemudian disempurnakan dengan Penetapan Presiden Nomor
104 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
5 Tahun 1960 yang khusus mengatur tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong. Peraturan Presiden ini menitikberatkan ketentuan yang berkaitan dengan kestabilan dan efisiensi pemerintahan daerah. Hal ini ditunjang dengan adanya penambahan beberapa elemen baru, seperti pemusatan pimpinan pemerintahan di tangan kepala daerah. Kepala daerah dibantu oleh Badan Pemerintah Harian (BPH). Sementara itu, DPRD yang diketua oleh kepala daerah bekerja menurut sistem demokrasi terpimpin.
Hal yang membedakan Peraturan Presiden ini dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 adalah adanya penyebutan daerah-daerah yang mengatur rumah tangganya sendiri. Berdasarkan ketentuan peraturan presiden ini, penyebutan nama daerah cukup hanya dengan menggunakan nama daerah saja, sedangkan untuk pemerintahannya disebut dengan pemerintah daerah. Untuk daerah kota, tetap dipergunakan nama daerah kota praja dan untuk pemerintahannya disebut dengan pemerintah daerah kota praja.65 Semua daerah kota praja setingkat dengan daerah tingkat II.
Pemerintah daerah pada era berlakunya peraturan pemerintah ini terdiri dari dua elemen utama, yaitu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kepala daerah beserta perlengkapannya merupakan elemen yang berdiri sendiri. Sementara itu, kedudukan dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disesuaikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat RI berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960. Kepala daerah tingkat I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Sementara itu, kepala daerah tingkat II diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan persetujuan presiden. Para calon kepala daerah diajukan oleh masing-masing DPRD dari daerah yang bersangkutan. Kepala daerah, karena jabatannya, menjadi Ketua DPRD dengan alasan bahwa diharapkan kepala daerah bisa menjadi sesepuh di daerahnya. Kebijakan ini menunjukkan bahwa dekonsentrasi sangat menonjol dalam sistem pemerintahan dan otonomi daerah.
Penyelenggaraan administrasi yang berhubungan dengan pemerintahan di daerah dilakukan oleh sekretaris daerah di bawah pimpinan kepada daerah. Sekretaris daerah dipilih oleh DPRD dari calon-calon yang diajukan oleh kepala daerah. Kepala daerah juga dibantu oleh
65 Terkecuali daerah Kota Praja Jakarta Raya yang dalam ketentuan sebelumnya
disebutkan setingkat dengan daerah tingkat I. Kondisi ini dilanjutkan dengan adanya Penetapan Presiden Nomor 2Tahun 1961 yang semakin mengukuhkan kedudukan Kota Praja Jakarta Raya sebagai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya. Utang Rosidin, Otonomi Daerah, 68.
IDENTITAS SOSIAL DALAM DEMOKRATISASI ... | 105
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
anggota Badan Pengurus Harian (BPH)66 yang tidak membantunya dalam hal sebagai alat pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan yang membantu pemerintahan umum pusat adalah pegawai-pegawai pemerintah pamong praja yang bersangkutan.
Pasca Dekrit Presiden, otoritas pemerintah pusat kembali memegang pimpinan. Tuntutan otonomi seluas-luasnya bergeser keharusan melaksanakan demokrasi sesuai dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan perwakilan (demokrasi terpimpin). Pada periode ini, ide yang dikembangkan adalah konsep masyarakat adil makmur secara materil dan spiritual, di bawah kerangka demokrasi terpimpin dalam segala sektor kenegaraan dan kemasyarakatan termasuk sektor pemerintah daerah dan hubungannya dengan pemerintah pusat. Suatu pemerintah daerah yang stabil dan efeisien yang mampu memberikan bantuan kepada pemerintah pusat untuk mencapai masyarakat adil makmur.
Pada periode selanjutnya, ditetapkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965. Pada dasarnya regulasi ini adalah penyempurnaan atau dalam beberapa literatur lain disebut dengan upaya pemantapan terhadap dua Penetapan Presiden yang sudah ada sebelumnya. Realitanya, sampai akhir tahun 1965 regulasi pemerintahan daerah yang ada masih dirasa kurang mewadahi dan masih menimbulkan kesimpangsiuran dalam penerapannya. Sementara itu, adanya Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1965 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Sementara Berencana tahapan Pertama Tahun 1961-1969 mengisyaratkan perlunya pembaharuan dan revisi terhadap ketentuan pemerintahan daerah dalam satu bentuk udang-undang khusus.
Setelah melalui proses yang cukup panjang, pada tanggal 1 September 1965 Presiden mengesahkan Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Keberadaan undang-undang ini secara tegas menegaskan pencabutan regulasi-regulasi yang mengatur pemerintahan daerah yang sudah ada sebelumnya, yaitu; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1959, Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1960 dan Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 jo. Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1965.
66 Keanggotaan BPH berjumlah sekurang-kurangnya sebanyak 3 oang dan
sebanyak-banyaknya adalah 5 orang yang terdiri dari mantan Anggota DPD yang dibubarkan dan bersedia. BPH ini diangkat dan diberhentikan menurut peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah yang diajukan oleh DPRD. Utang Rosidin, Otonomi Daerah, 69.
106 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam regulasi ini, wilayah Negara dibagi menjadi tiga tingkatan daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Setiap tingkatan daerah tersebut diberikan nama khusus, sebagai berikut.
a. provinsi dan/atau kota karya untuk menyebut daerah dan/atau kota yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri pada tingkat I;
b. kabupaten dan/atau kotamadya untuk menyebut daerah dan/atau kota yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri pada tingkat II, dan;
c. kecamatan67 dan/atau kota praja untuk daerah dan/atau kota yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri pada tingkat III.
Alat pemerintahan daerah, sebagaimana yang dijelaskan dalam
ketentuan Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 terdiri dari kepala daerah dan DPRD serta terdapat wakil kepala daerah, BPH dan sekretaris daerah. Sebagai alat perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, kepala daerah mempuyai beberapa tugas sebagai berikut.
a. memegang pimpinan kebijakan politik polisional di daerahnya dengan mengindahkan wewenang para pejabat yang bersangkutan berdasarkan peraturan yang berlaku;
b. melaksanakan koordinasi antarjawatan pemerintah pusat di daerah dan antarjawatan tersebut dengan pemerintah daerah;
c. melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintah daerah, dan; d. melakukan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh pemerintah
pusat.
Kepala daerah tidak hanya mempunyai tugas selaku alat dari pemerintah pusat, namun juga bertugas selaku alat pemerintah daerah dengan rincian sebagai berikut;
a. memimpin pelaksanaan kekuasaan eksekutif pemerintah daerah, baik dalam sektor rumah tangga daerah ataupun dalam tugas pembantuan;
b. menandatangani peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh DPRD, dan;
67 Apabila dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948,
penggunaan nama untuk daerah tingkat I dan II masih sama. Hanya saja pada Undang-undang ini, untuk daerah tingkat III dinamakan dengan kecamatan, bukan desa seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948.
IDENTITAS SOSIAL DALAM DEMOKRATISASI ... | 107
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
c. mewakili daerahnya untuk urusan di dalam dan di luar pengadilan, jika perlu kepala daerah dapat menunjuk sorang kuasa hukum untuk mewakilinya.
Berdasarkan regulasi ini, kebijakan otonomi daerah dititik-
beratkan pada asas desentralisasi dengan memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah. Sementara itu, asas dekonsentrasi diterapkan hanya sebagai pelengkap. Pada masa ini, pengawasan dilakukan dalam 3 bentuk, yaitu pengawasan umum, preventif dan represif. pengawasan represif dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atau penguasa yang ditunjuknya dan oleh KDH sebagai alat pemerintah pusat di daerah. Pengawasan preventif dilakukan oleh instansi pengawas secara bertingkat.
4. Era Orde Baru
Pergantian rezim penguasa dari era orde lama ke orde baru membawa perubahan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Demikian juga halnya terhadap regulasi yang mengatur otonomi daerah. Sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 tahun 1965, ditetapkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Regulasi ini lahir setelah ada pengarahan politis mengenai pemerintahan daerah dalam Garis-garis Besar haluan Negara (GBHN). Regulasi ini lahir sebagai pelaksana dari Tap MPR RI Nomor IV Tahun 1973 dan mulai berlaku sejak 23 Juli 1974 hingga 6 Mei 1999. Regulasi ini dinilai sangat sentralistis dan kurang memperhatikan kedudukan DPRD sebagai badan legislatif daerah yang berdiri sendiri.
Ada beberapa struktur politik rezim orde baru yang sentralistis dan otoriter yang membawa pengaruh terhadap eksistensi pemerintah daerah,68 sebagai berikut.
a. pembentukan sejumlah lembaga represif, seperti; Kopkantib, Opsus dan Bakin. Hal ini merupakan strategi politik rezim orde baru untuk mengamankan kebijakan-kebijakan otoritas penguasa. Langkah ini bertujuan untuk melakukan pemantauan terhadap kondisi sosial kemasyarakatan. Dengan adanya pemantauan seperti ini, otoritas orde baru mempunyai keleluasaan dalam mengambil kebijakan terhadap lawan politiknya;
b. depolitisasi masyarakat guna memarginalkan kehidupan politik masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan berbagai cara, seperti; floating mass (massa mengambang), mengadakan pemilihan
68 Penjelasan lebih lanjut lihat Martin Jimung, Politik Lokal, 181-185.
108 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
umum untuk melegitimasi formal, pengebirian eksistensi partai-partai politik, kontrol ketat terhadap kehidupan politik, dominasi militer dan birokrasi sakraliasi Soeharto.
Ketentuan dalam regulasi ini menyebutkan bahwa daerah yang
berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya disebut sebagai daerah otonom yang selanjutnya disebut dengan daerah. Ketentuan ini juga memperkenalkan dua tingkatan daerah, yaitu daerah tingkat I dan daerah tingkat II. Untuk memberikan pertimbangan kepada presiden mengenai pembentukan daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah, dibentuklah dewan pertimbangan otonomi daerah yang beranggotakan beberapa orang menteri dan diketuai langsung oleh Menteri Dalam Negeri.
Regulasi ini juga memberikan bentukan baru dalam hal pembagian daerah pemerintahan. Daerah-daerah yang ada dalam negara dibagi menjadi wilayah provinsi dan wilayah ibukota negara. Wilayah provinsi kemudian dibagi lagi menjadi beberapa wilayah kabupaten/kotamadya. Selanjutnya, wilayah kabupaten/kotamadya dibagi lagi menjadi beberapa wilayah kecamatan. Titik berat otonomi daerah pada masa ini adalah daerah tingkat II yang mempunyai hubungan langsung dengan masyarakat sehingga diharapkan bisa lebih menampung aspirasi langsung dari rakyat. Kepala wilayah adalah penguasa tunggal dalam bidang pemerintahan, dalam artian lain bahwa kepala pemerintahan mengkoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang.
Apabila dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, pada dasarnya Indonesia masih menganut sistem otonomi seluas-luasnya secara fleksibel dalam hal mengikuti perkembangan masyarakat sesuai kebutuhan daerahnya masing-masing. Prinsip otonomi dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 pepemberian otonomi kepada daerah didasarkan pada perhitungan, tindakan dan kebijaksanaan yang benar-benar dapat menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata dapat bertanggung jawab.69 Disebut bertanggung jawab dalam artian bahwa pemberian otonomi harus benar-benar sejalan dengan tujuan untuk melancarkan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok negara.
69 Pada dasarnya, regulasi ini bersifat limitatif atau dalam beberapa literatur lain banyak juga ditemukan ungkapan otonomi setengah hati. Hal ini dapat dipahami dari penggunaan 3 asas, yaitu; desentraliasi, dekonsentrasi dan pembantuan, yang secara bersama-sama dengan seimbang dan serasi. Penggunaan ketiga asas ini semakin mengaburkan makna otonomi daerah dala prakteknya, pemerintah pusat lebih menitik-beratkan pada pelaksanaan asas dekonsentrasi. B.N. Marbun, Otonomi Daerah, 90.
IDENTITAS SOSIAL DALAM DEMOKRATISASI ... | 109
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Regulasi ini tidak mengatur secara rinci dan tegas tentang hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan daerah. Ketentuannya hanya menyebutkan bahwa daerah berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur rumah tangganya sendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut beberapa ahli, ketentuan ini dinilai sebagai pasal “karet” yang sewaktu-waktu dapat dirubah, diganti, ditambah dan dikurangi oleh pemerintah.70 Implementasi prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, seperti yang dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, mengalami beberapa kendala, sebagai berikut.
a. desentralisasi tidak berjalan dikarenakan kuatnya pengaruh praktek sentraliasi, desentralisasi berlaku hanya pada wilayah pelaksanaan saja sedangkan hal-hal lain masih di bawah kendali pemerintah pusat. Demikian juga halnya dengan dekonsentrasi dan tugas pembantuan lebih banyak dijalankan daripada desentralisasi;
b. pengawasan yang dilaksanakan dengan sangat ketat, dan; c. tidak berimbangnya pembagian keuangan dan hasil perekonomian
bagi daerah.
5. Era Reformasi Hingga Saat Ini Pergantian rezim pemerintahan dari rezim orde baru ke rezim
reformasi di Indonesia membawa perubahan terhadap karakteristik pemerintahan. Era reformasi memberikan peluang besar untuk kembali menerapkan otonomi secara luas. Pada era ini, ancaman disintegrasi bangsa menjadi sangat rawan. Banyak daerah yang menuntut untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia, bibit-bibit separatisme mulai tumbuh.71 Regulasi yang pertama kali ditetapkan pada rezim reformasi72 adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2001.
Regulasi ini beserta Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 merupakan koreksi total terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dalam upaya memberikan otonomi yang cukup luas kepada daerah sesuai dengan cita-cita Undang-undang Dasar 1945. Regulasi ini merupakan pelaksanaan Tap MPR RI Nomor XV/MPR/1998. Regulasi ini memberikan kesan adanya pergeseran pendulum secara ekstrim yang
70 B.N. Marbun, Otonomi Daerah, 92. 71 Utang Rosidin, Otonomi Daerah, 73. 72 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dibuat untuk memenuhi tuntutan
reformasi, yaitu mewujudkan Indonesia baru yang lebih demokratis, lebih adil dan lebih sejahtera. Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala
Daerah Secara Langsung (Jakarta: Raja Grafingdo Persada, 2011), 1.
110 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
disesuaikan dengan kondisi politik pada waktu tersebut.73 Pergeseran ekstrim yang dimaksud adalah pergeseran pendulum yang cukup drastis dari kondisi sentralistis menuju arah desentraliasi yang yang lebih luas cakupannya. Selama ini, hubungan pemerintah pusat dengan daerah sangat sentralistis.74 Dengan diberlakukannya regulasi ini, hubungan pemerintah pusat dengan daerah lebih bersifa desentralistis, dalam artian sebagian wewenang dalam bidang pemerintahan diserahkan kepada daerah.
Undang-undang ini mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan asas desentralisasi. Hal-hal mendasar adalah adanya upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, penumbuhan prakarsa dan kreativitas, peningkatan peranan masyarakat serta pengembangan peranan DPRD. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, regulasi ini juga diiringi dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Berlandaskan pada kedua regulasi tersebut, daerah diberikan kesempatan secara luas untuk mengatur daerahnya dengan ditopang oleh pendanaan yang lebih memadai. Berbeda dengan undang-undang yang ada sebelumnya, undang-undang ini juga mengatur pemerintahan desa seperti yang dulu juga pernah diatur secara tersendiri.
Regulasi ini menganut sistem otonomi formal meskipun tidak dijelaskan secara implisit. Hal ini dapat dipahami dari prinsip pemberian otonomi yang seluas-luasnya yang diindikasikan dari adanya pembagian kewenangan dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam bagian Penjelasan Undang-undang ini disebutkan ada beberapa pokok pikiran yang menjadi dasar penetapan regulasi ini, sebagai berikut.
a. sistem ketatanegaraan Indonesia wajib menjalankan prinsip pembagian kewenangan berdasarkan asas desentralisasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. daerah yang dibentuk atas asas desentraliasi dan dekonsentrasi adalah daerah provinsi, sedangkan daerah yang dibentuk atas dasar desentralisasi adalah daerah kabupaten dan daerah kota. Daerah yang dibentuk atas asas desentralisasi berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat;
c. daerah yang berada di luar daerah provinsi dibagi dalam daerah otonom, sehingga dengan demikian maka wilayah administrasi
73 B.N. Marbun, Otonomi Daerah, 101. 74 Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi, 1.
IDENTITAS SOSIAL DALAM DEMOKRATISASI ... | 111
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
yang berada dalam daerah kabupaten dan kota dapat dijadikan daerah otonom atau dihapus, dan;
d. kecamatan yang menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah merupakan wilayah administrasi dalam rangka dekonsentrasi, menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah kedudukannya diubah menjadi perangkat daerah kabupaten atau daerah kota.
Merujuk pada regulasi ini, wilayah Republik Indonesia dibagi
menjadi daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang bersifat otonom. Daerah provinsi berkedudukan juga sebagai wilayah administrasi. Regulasi ini tidak mengenal adanya istilah daerah tingkat I dan daerah tingkat II, sedangkan kotamadya berubah menjadi kota. Kewenangan yang ada di daerah mencakup seluruh kewenangan dalam bidang pemerintahan kecuali dalam hal politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama dan beberapa kewenangan yang meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservatif dan standarisasi internasional.
Susunan pemerintahan daerah berdasarkan regulasi ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai badan legislatif daerah dan Pemerintah Daerah terdiri dari kepala daerah beserta perangkatnya selaku badan eksekutif daerah. Berdasarkan uraian dalam ketentuan Undang-undang ini, dapat diperhatikan beberapa prinsip-prinsip dasar pemberian otonomi daerah,75 sebagai berikut.
a. penyelenggaraan otonomi daerah didasarkan pada aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi dan keberagaman daerah;
b. pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab;
c. pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diberikan pada daerah kabupaten dan kota, sedangkan otonomi yang diberikan kepada provinsi adalah otonomi yang terbatas;
75 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Rafa Grafindo
Persada, 2005), 337.
112 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
d. pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap menjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antardaerah;
e. pelaksanaan otonomi daerah haruslah meningkatkan kemandirian daerah otonom.76
Perubahan undang-undang ini membawa dampak besar bagi keadaan di daerah, seperti kemandirian daerah dalam menentukan arah pembangunannya yang disesuaikan dengan kultur masyarakat, perkembangan dan kemampuan masyarakat setempat. Secara umum, regulasi ini membawa banyak kemajuan bagi daerah dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini disebabkan pemerintah daerah diberikan wewenang yang luas dalam mengelola dan mengembangkan kekayaan daerag guna dimanfaatkan untuk pembangunan di daerah.
Pergolakan sosial politik yang terjadi pada era reformasi ternyata mempengaruhi penerapan undang-undang ini. Pada awalnya, regulasi ini diharapkan dapat membawa angin segar bagi pemerintah di daerah akan tetapi dalam perkembangannya regulasi ini dirasa masih belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Hal ini mendorong adanya beberapa masukan baru dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Kondisi ini juga diakibatkan adanya amandemen terhadap Undang-undang Dasar 1945, terutama dengan lahirnya regulasi yang berkaitan tentang pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat.77 Aspirasi yang muncul dari daerah adalah adanya desakan untuk melaksanakan pemilihan kepada daerah secara langsung. Kondisi ini tidak sesuai dengan apa yang dicantumkan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.
Era pemerintahan setelah berakhirnya orde baru melakukan banyak revisi terhadap banyak peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan salah satu program reformasi dalam bidang hukum adalah perubahan terhadap peraturan perundang-undangan. Perubahan ini diupayakan dalam rangka membangun sistem hukum nasional yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan hukum yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2004-2009.
76 Oleh sebab itu, dalam daerah kabupaten dan kota tidak terdapat lagi wilayah
administrasi. Demikian juga halnya dengan kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah dan pihak lain, seperti; badan otoritas, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawansan perkotaan baru, kawasan pariwisata dan lain sebagainya berlaku ketentuan peraturan daerah otonom. Utang Rosidin, Otonomi Daerah, 75.
77 Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas, 2.
IDENTITAS SOSIAL DALAM DEMOKRATISASI ... | 113
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Perubahan substansi hukum juga terjadi pada regulasi yang mengatur masalah pemerintah daerah. Revisi terhadap regulasi ini tidak hanya muncul karena kurang tersalurkannya aspirasi masyarakat daerah, akan tetapi juga dalam rangka menyesuaikan sistem ketata-negaraan Indonesia yang merujuk pada konstitusi pasca amandemen, terutama hal-hal yang berkaitan dengan pemerintah daerah. Berkaitan dengan ini, disahkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang secara tegas dalam pasal 239 menyatakan bahwa dengan diberlakukannya undang-undang ini maka Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.
Regulasi ini semakin mempertegas hubungan hierarkis antara kabupaten/kota dan provinsi, antara provinsi dengan pemerintah pusat berdasarkan asas kesatuan administrasi dan kesatuan wilayah. Berdasarkan asas kesatuan dan asas wilayah, pemerintah pusat berhak melakukan koordinasi, supervisi dan evaluasi terhadap pemerintahan di bawahnya, demikian juga halnya dengan pemerintah provinsi terhadap pemerintah kabupaten/kota. Demikian juga halnya dengan kedudukan kepala daerah yang disejajarkan dengan kedudukan DPRD.
Penerapan otonomi daerah berdasarkan regulasi ini tetap menggunakan prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.78 Otonomi luas dimaksdukan bahwa kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat sehingga isi otonomi yang suatu daerah memiliki keragaman yang bervariasi. Di samping itu, daerah juga diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah itu sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing.
Prinsip otonomi nyata maksudnya adalah penyelenggaraan suatu tugas, wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Sehingga isi otonomi suatu daerah tidak sama dengan daerah lainnya. Otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk menigkatkan kesejahteraan rakyat.
Dalam proses negara sebagai sebuah sistem, maka kedudukan pemerintah daerah adalah sebagai subsistem dan merupakan badan
78 Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas, 4-6.
114 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
operasional Negara yang berhubungan dan berhadapan dengan warga negara. Dalam rangka penyelenggaraan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, regulasi ini menegaskan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kecuali yang dalam undang-undan ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus diri sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah daerah dapat menyelenggarakan sendiri atau melimpahkan sebagian urusan pemerintah kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah, atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa.
Hal lain yang memberikan perbedaan signifikan antara Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan regulasi yang sudah ada sebelumnya adalah adanya ketentuan yang mengatur pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Hal ini sesuai dengan tuntutan reformasi dan merupakan konsekuensi logis perubahan tatanan kenegaraan seiring terjadinya amandemen Undang-undang Dasar 1945.79 Untuk menunjang progresivitas dan efektifitas pelaksanaa otonomi daerah, maka regulasi ini kemudian dilengkapi dengan disahkannya Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.
Ketentuan baru yang diatur dalam undang-undang ini adalah adanya kemungkinan pembentukan daerah baru, penghapusan dan penggabungan daerah serta adanya kawasan khusus. Ketentuan ini dibuat dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di samping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Pada prinsipnya, pembentukan daerah baru dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau atau daerah yang bersandingan. Sementara itu, pemekaran daerah adalah pembagian satu wilayah menjadi beberapa wilayah baru, seperti; pemekaran terhadap Provinsi Jawa Barat yang pada saat sekarang menjadi Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Pelaksanaan pembentukan daerah baru ini diharuskan memenuhi syarat administratif, teknis dan fisik sebagaimana yang dijelaskan secarar rinci dalam undang-undang.
Hal yang sama juga berlaku dalam upaya penghapusan atau penggabungan daerah. Sebuah daerah dihapuskan atau digabungkan apabila daerah tersebut tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah
79 Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas, 5.
IDENTITAS SOSIAL DALAM DEMOKRATISASI ... | 115
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
sebagaimana mestinya. Proses penghapusan/penggabungan ini dilakukan setelah melalui proses evaluasi terhadap indikator-indikator yang mempengaruhi daerah tersebut. Demi menjaga ketertiban dan rasa keadilan, maka penghapusan dan penggabungan daerah tersebut ditetapkan melaui Undang-undang. Sedangkan terkait masalah batas daerah, perubahan nama daerah atau pemindahan ibukota yang tidak mengakibatkan penghapusan atau penggabungan daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IV FORMALISASI NILAI ADAT MINANGKABAU
DALAM BENTUK SISTEM PEMERINTAHAN NAGARI
Bab ini mengkaji konsep formalisasi nilai-nilai tradisional adat Minangkabau dalam bentuk hukum positif yang diakui. Proses pengakuan ini menempuh jalur politik hukum yang panjang, mulai dari pengakuan pada tingkat pusat hingga masa pembentukan beragam regulasi pada tingkat daerah. Pada bagian ini, dipaparkan materi-materi positivisasi nilai-nilai adat tradisional dalam bentuk sistem pemerintahan nagari beserta beberapa regulasi yang sudah ditetapkan dan berkaitan dengan nilai-nilai positivisasi tersebut. Materi-materi tersebut terkait dengan eksistensi nagari sebagai lembaga pemerintahan formal dan kultural masyarakat hukum adat Minangkabau, Pemeritahan Nagari dan finansial nagari serta hak ulayat nagari. Pelaksanaan sistem pemerintahan nagari akan dikomparatifkan dengan sistem pemerintahan sebelumnya sehingga dapat disimpulkan efektivitasnya terhadap masyarakat. A. Formalisasi Nilai-nilai Adat Tradisional Minangkabau
Persilangan identitas agama dan etnik1 yang merupakan bagian dari hak-hak budaya dan hak komunitas atas identitas kultural merupakan sesuatu yang jarang sekali dibahas dalam kajian pluralisme. Hak asasi kultural manusia (cultural rights)2 merupakan hak-hak mendasar yang
1 Sebuah peradaban terbangun dari dialektika manusia dengan realitas di satu
pihak dan dialognya dengan teks pada pihak lain. Nilai-nilai kultural-lokal masyarakat akan menjadi variabel utama yang tidak bisa diabaikan begitu saja, di samping keberadaan teks. Kondisi ini sangat mempengaruhi pola relasi yang terbangun antara agama dan kebudayaan lokal. M. Khoirul Muqtafa, “Rekonsiliasi Kultural Islam dan Budaya Lokal”, dalam Nilai-nilai Pluralisme dalam Islam: Bingkai Gagasan yang
Berserak, ed. Sururin (Bandung: Nuansa, 2005), 51. 2 HAM kultural mengakomodasi hak-hak komunitas atas identitas kultural dan
harus mendapatkan jaminan dan perlindungan dari negara. Dalam artian lain, Negara harus bertanggung jawab untuk mempromosikan (to promote), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfill) segenap hak-hak mendasar bagi warga negara tanpa ada
118 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
dimiliki warga negara selaku individu dan/atau komunitas yang bebas untuk menentukan sendiri agama, tradisi, kepercayaan, adat dan keyakinannya tanpa gangguan, intervensi dan pengekangan yang diakibatkan oleh negara ataupun aktor-aktor non-negara (non-state
actors). HAM kultural merupakan pengakuan terhadap hak-hak komunitas untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dengan bebas. Hak ini sudah diakui dalam Konvenan Hak-hak Sipil dan Politik serta Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
Kebudayaan3 dalam hak asasi manusia bukanlah persoalan simbolik, berkesenian dan berkegiatan ilmiah. Lebih dari itu, kebudayaan merupakan persoalan hak hidup bagi komunitas yang terus menerus diperjuangkan dan dipertahankan (the right to live) baik dalam kehidupan politik, sipil (keperdataan), ekonomi, sosial maupun dalam kehidupan budaya. Dalam hubungannya dengan permasalahan keagamaan, agama sebagai poros utama akan berhadapan dengan kebudayaan lokal yang merupakan hasil kreasi dan rekayasa manusia.4 Agama sebagai sebuah tatanan nilai tidaklah berdiri sendiri, namun juga bersandingan dengan aspek lainnya. Dalam artian lain, agama berhadapan dengan fenomena pluralitas budaya yang berserak.
Merujuk pada realitas sosial relasi antara budaya dan agama, selayaknya diarahkan pada upaya rekonsiliasi kultural, bukan rekonsiliasi
diskriminasi, peminggiran ataupun pengucilan. Ahmad Baso, “Agar Tidak Memayoritaskan Diri: Tentang Islam, Pluralisme & HAM Kultural”, dalam Nilai-nilai
Pluralisme dalam Islam: Bingkai Gagasan yang Berserak, ed. Sururin (Bandung: Nuansa, 2005), 28.
3 Kebudayaan, sebagaimana yang dijelaskan dalam cultural studies merupakan arena di mana komunitas melakukan negosiasi dan resistensi terhadap kekuatan-kekuatan dominan dan juga sebagai mekanisme untuk mengklaim atau menuntut hak-haknya. Kebudayaan merupakan segenap totalitas kehidupan manusia tempat mereka memaknai dan menyikapi identitas mereka dalam pergumulan sosial politik yang terjadi di sekitarnya. Ahmad Baso, “Agar Tidak Memayoritaskan Diri”, 29.
4 Terkait dengan hal ini, Thomas F. O’Dea, sebagaimana yang dijelaskan kembali oleh M. Khoirul Muqtafa menguraikan bahwa relasi antara agama dan budaya secara khusus telah berlangsung dalam beberapa fase utama. Fase pertama atau yang sering juga diistilahkan dengan antocracy atau cosmic totally adalah ketika agama dan budaya dipandang sebagai dua komponen utama yang sulit dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Agama dan kebudayaan bersentuhan secara intens sehingga sulit melakukan diferensiasi antara nilai-nilai keagamaan dengan nilai-nilai budaya. Fase kedua adalah ketika agama dan budaya mulai mengalami diferensiasi struktural dalam bentuk institusinya masing-masing. Pada fase ini seringkali terjadi kekaburan antara peran dan wilayah di antara keduanya. Fase ketiga adalah ketika diferensiasi agama dan budaya itu semakin transparan, tersendiri dan jarang berinteraksi. M. Khoirul Muqtafa, “Rekonsiliasi Kultural Islam”, 52-53.
FORMALISASI NILAI ADAT MINANGKABAU ... | 119
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
politik. Rekonsiliasi kultural merupakan rekonsiliasi dengan upaya mempertahankan hak-hak kultural masyarakat lokal, terutama yang berkaitan dengan relasi agama dan budaya lokal. Rekonsiliasi kultural ini memungkinkan upaya untuk saling menopang dan melestarikan antara agama dan budaya lokal. proses ini tidak berjalan secara koeksistensi, namun secara proeksistensi yang terimplementasikan dalam tindakan-tindakan dan aksi-aksi yang jelas dalam kehidupan sehari-hari sehingga kolaborasi di antara keduanya menjadi lebih acceptable dalam masyarakat.5 Pada saat ini, sudah ada instrumen HAM Internasional yang merupakan penyempurnaan dari naskah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Awalnya merupakan deklarasi terhadap hak-hak perempuan, tentang hak-hak anak disusul dengan hak-hak masyarakat adat atau indigenous peoples. Regulasi ini kemudian diikuti dengan adanya dua konvenan utama terkait hak-hak sipil dan politik dalam ICCPR dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dalam ECOSOC.
Penggunaan term indigenous peoples yang diidentikkan dengan masyarakat adat mengalami rentetan proses yang panjang. Hal ini dipengaruhi oleh upaya mencari padanan bahasa yang tepat dalam penggunaannya di tingkat internasional. Defenisi mengenai tribal peoples dalam Konvensi 169 ILO6 relatif lebih dekat dengan realitas hukum dan sosial di Indonesia. Akan tetapi, sejumlah anggota masyarakat adat menolak penggunaan term tribal peoples dengan alasan adanya
5 M. Khoirul Muqtafa, “Rekonsiliasi Kultural Islam”, 62. 6 Sebutan untuk masyarakat adat cenderung merupakan terjemahan dari term
indigenous people atau tribal people menjadi perbincangan dalam kancah internasional. Arianto Sangaji, “Kritik Terhadap Gerakan Masyarakat Adat Indonesia” dalam Adat
dalam Politik Indonesia, eds. Jamie S. Davison, et.all. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), 348. International Labour Organization (ILO), sebuah badan antarpemerintahan dengan struktur tripatrit yang terdiri dari perwakilan pemerintah, pengusaha-pengusaha nasional dan organisasi-organisasi buruh telah memperbincangkan posisi pekerja dari kalangan penduduk asli (indigenous worker) sejak tahun 1920-an. Hal ini terlihat dengan diperkenalkannya perjanjian pertama tentang Indigenous and Tribal Population atau yang dikenal juga dengan Konvensi ILO 107. Konvensi ini kemudian direvisi menjadi Konvensi ILO 169 yang ditetapkan pada tahun 1989. B. Kingsbury, “Indigenous People as an International Legal Concept” dalam Indigenous People of Asia, eds. R.H. Barnes dan B. Kingsbury (Michigan: Association for Asian Studies, 1995), 14. Term yang sama juga dipergunakan oleh Bank Dunia sejak tahun 1982 untuk menggambarkan spektrum kelompok sosial yang luas, meliputi: indigenous ethnic minoritites, tribal groups dan scheduled tribes. Penjelasan lebih lanjut dalam S.H. Davis dan L.T. Soeftestad, “Participation and Indigenous People” dalam Social Development Paper 9 (Washington D.C.: World Bank, 1995), 31.
120 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
pandangan negatif terhadap term tersebut.7 Golongan ini memilih untuk menggunakan term indigenous peoples sebagai padanan yang sesuai untuk menggambarkan masyarakat adat.
Kejatuhan rezim otoriter dan sentralistik mendorong terjadinya gelombang dan langkah-langkah desentralisasi. Penetapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah berdampak pada beberapa daerah di Indonesia mulai melakukan inisiatif-inisiatif untuk mengembangkan potensi daerahnya masing-masing,8 mulai dari gegapnya pemilihan kepala daerah hingga hingar-bingar membentuk identitas daerah masing-masing. Sekalipun sejumlah administrasi daerah masih tetap meneruskan tradisi Orde Baru tentang pengakuan bersyarat atas kelompok masyarakat adat beserta hak-haknya, di bawah bendera desentralisasi beberapa daerah berusaha membentuk peraturan-peraturan yang lebih responsif.9 Dalam konteks Sumatera Barat,10 salah satu kebijakan daerah yang dikembangkan adalah kembali menerapkan bentuk pemerintahan nagari. Sebagian besar kalangan menganggap kebijakan tersebut sangat positif dan strategis karena akan terjadi desentralisasi kewenangan dari era
7 Pada dasarnya ada banyak term yang dipergunakan untuk masyarakat adat
dalam berbagai regulasi yang ada di Indonesia, seperti: orang Indonesia asli, volksgemenschap, dan rechtsgemeenschappen. Sandra Moniaga, “Dari Bumiputera Ke Masyarakat Adat: Sebuah Perjalanan Panjang dan Membingungkan”, dalam Adat dalam
Politik Indonesia, eds. Jamie S. Davison, et.all. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), 306-307.
8 Dalam penerapan otonomi daerah dan pembangunan daerah, pengungkapan sejarah lokal menjadi sangat penting untuk dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengontrol pelaksanaan otonomi daerah agar tidak melenceng dari koridor yang semestinya. Indriyanto, “Otonomi dan Pembangunan di Daerah”, makalah yang disampaikan dalam Konfrensi Nasional Sejarah VII pada 28-31 Oktober 2001 di Jakarta.
9 Sandra Moniaga, “Dari Bumiputera Ke Masyarakat Adat”, 319. 10 Pengidentikkan Keresidenan Sumatera Barat dengan daerah budaya
Minangkabau pada tahun 1905 mendapat sambutan positif dari kalangan penghulu. Kelompok ini menyatakan bahwa hal tersebut merupakan langkah awal dalam mewujudkan Sumarak Alam Minangkabau (Minangkabau Raya). Taufik Abdullah, “Modernization in the Minangkabau World: West Sumatera in Early Decades of the 20 Century”, Culture and Politics in Indonesia, ed. Claire Holt (Itacha and London: Cornell University Press, 1972), 216. Kerjasama antara kaum adat dengan pemerintah pada masa itu menggiring satu pandangan bahwa Sumatera Barat merupakan sebuah keutuhan wilayah kaum adat. Keinginan meminagkabaukan Sumatera Barat juga muncul pada pertengahan dekade 1920-an ketika pemerintahan Hindia Belanda berencana mereorganisasi pemerintahannya di Sumatera. Gusti Asnan, Memikir Ulang
Regionalisme: Sumatera Barat Tahun 1950-an (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 11-12
FORMALISASI NILAI ADAT MINANGKABAU ... | 121
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
sebelumnya yang sentralistis, menuju keterwujudan pemerintah daerah yang lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal.
Selain untuk keperluan desentralisasi kekuasaan atau kewenangan dalam pengertian geografis, dengan kembali pada sistem pemerintahan bernagari, juga diharapkan the land of Minangkabau, dengan adagium adat adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, syarak mangato
adat mamakai dimana nagari-nagari menjadi lebih berdaya dengan diperankannya kembali ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai selaku kontrol sosial di tengah masyarakat, namun juga identitas keislaman dapat diwujudnyatakan.
Perdebatan kemudian muncul nagari model apa dan kapan yang kemudian akan dirujuk, karena sistem pemerintahan nagari telah mengalami dinamisasi. Dinamisasi bentuk pemerintahan nagari ini sangat dipengaruhi oleh kondisi pemerintahan dimulai dari sebelum datangnya bangsa asing seperti Islam dan Barat, zaman Orde Lama, masa Orde Baru. Persoalan lainnya yang kemudian muncul, pada satu sisi ada tuntutan menggebu bagaimana Sumatera Barat dalam pengertian Minangkabau tetap menjadi otentik, karena Sumatera Barat adalah daerah yang secara turun-temurun telah mempunyai kedekatan yang sangat kuat antara adat dengan agama. Kedekatan ini cukup mengikat dan menyatu. Agama menjadi tergantung pada adat atau tradisi setempat. Demikian juga sebaliknya, adat atau tradisi mendapatkan muatan agama. Beberapa kasus di daerah tertentu menunjukkan adanya kesatuan antara adat dan agama yang berakibat pada kesamaan sikap adat dengan sikap agama, atau sikap agama terhadap persoalan setempat menjadi sama dengan sikap adat. Sementara itu realitas di tengah masyarakat menunjukkan adanya perubahan yang signifikan, masyarakat Sumatera Barat seperti halnya masyarakat lainnya dihadapkan dengan modernisasi berikut segala konsekuensinya yang menuntut terjadinya perubahan yang lebih dinamis.
Masyarakat hukum adat Minangkabau yang ada di Sumatera Barat merupakan kelompok etnis yang unik dan terkenal karena keahlian berdagang dan prestasi intelektual mereka. Mereka ditandai dengan tiga ciri besar, yaitu: penganutan yang kuat terhadap Islam, kepatuhan terhadap sistem kekeluargaan matrilineal dan kecenderungan merantau atau bermigrasi yang kuat.11 Islam merupakan aspek penting lain dalam alam Minangkabau. Hubungan adat dan Islam dalam alam Minangkabau digambarkan dalam lambang kelengkapan sebuah nagari. Lambang nagari di Minangkabau adalah balai adat dan mesjid. Sebuah nagari dianggap
11 Azyumardi Azra, Surau: Pendidikan Islam Tradisional Dalam Transisi dan
Modernisasi (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003), 31.
122 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
tidak lengkap dan tidak sempurna apabila salah satu dari kedua institusi tersebut tidak ada. Balai adat merupakan lembaga kebudayaan, sedangkan mesjid merupakan lembaga keagamaan. Kedudukan mesjid di samping balai adat merupakan pernyataan keharmonisan antara ninik mamak dengan alim ulama dalam masyarakat Minangkabau.12
Hubungan antara adat dengan Islam, atau akhir-akhir ini antara adat, Islam dan negara,13 bervariasi sepanjang sejarah. Pada era prakolonial, Islam terutama diadaptasikan dengan adat matrilineal. Kondisi ini mengalami perubahan pada masa Perang Paderi, ketika para Islamis menyodorkan blue-print mereka sendiri untuk organisasi sosial, ekonomis dan politis. Kondisi tersebut kemudian mengalami perubahan ketika kolonial Belanda melakukan intervensi dan mendukung adat dalam melawan Islam.14 Dualitas adat dan Islam merupakan salah satu poin identifikasi sentral dan konstitutif bagi sebagian besar masyarakat Minangkabau. Kesatuan adat dan Islam yang tak terpisahkan diekspresikan dalam pepatah adat basandi syarak, syarak basandi
Kitabullah (adat berdasarkan syarak, syarak berdasarkan Alquran) atau yang biasa disingkat dengan ABSSBK. Antara tahun 2002 dan 2003, tiga konfrensi dilaksanakan dan memunculkan beberapa penerbitan yang terkait dengan konsep ABSSBK ini. Keyakinan bahwa adat dan Islam
12 Sidi Gazalba, Mesjid: Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam (Jakarta: Pustaka
Antara, 1983), 291. 13 Dalam tradisi pemikiran klasik dan pertengahan, hubungan agama (Islam)
dan negara merupakan sesuatu yang saling melengkapi, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan. Agama membutuhkan negara dan demikian juga sebaliknya. Sukron Kamil, Pemikiran Politik Islam Tematik: Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syariah
dan HAM, Fundamentalisme dan Antikorupsi (Jakarta: Kencana, 2013), 3-4. Al Mawardi menjelaskan bahwa kepemimpinan politik dalam Islam didirikan untuk melanjutkan tugas-tugas kenabian dalam memelihara agama dan mengelola kebutuhan duniawi masyarakat. Al Mawardi>, al Ah}ka>m al Sult}a>niyah (Beirut: Da>r al Fikr, t.th), 5. Penjelasan lebih lanjut dapat disimak dalam Hsin-Huang Michael Hsiao, “Islam and The State: Teachings and The Political Reality”, Islam in Contention: Rethinking Islam and
State in Indonesia, eds. Ota Atsushi, Okamoto Masaaki & Ahmad Suaedy (Jakarta: Wahid Institute - CSEAS - CAPAS, 2010), 27-32. Terkait dengan konteks keberadaan Peraturan Daerah yang bermuatan syariat Islam, dikaji lebih lanjut dalam Abubakar Eby Hara, “Pancasila and The Perda Syariah Debates in The Post-Soeharto Era: Toward A New Political Consensus”, dalam Islam in Contention: Rethinking Islam and State in Indonesia, eds. Ota Atsushi, Okamoto Masaaki & Ahmad Suaedy (Jakarta: Wahid Institute - CSEAS - CAPAS, 2010), 35-70.
14 Franz & Keebet von Benda-Beckmann, “Identitas-identitas Ambivalen: Desentralisasi dan Komunitas-komunitas Politik Minangkabau”, dalam Politik Lokal di
Indonesia, eds. Henk Schulte Nordholt & Gerry van Klinken (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), 561.
FORMALISASI NILAI ADAT MINANGKABAU ... | 123
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
tidak terpisahkan, bahwa nilai-nilai keduanya harus mengatur kehidupan masyarakat Minangkabau dan dengan adanya kemerosotan mereka, harus direvitalisasikan. Kondisi ini juga terdeskripsikan dalam semangat kembali ke nagari, kembali ke surau.
Kebijakan desentralisasi telah merangsang perdebatan-perdebatan mengenai pola hubungan antara adat, Islam dan negara. Kondisi ini tidak hanya berimbas pada pemerintahan desa, namun juga pada identitas masyarakat hukum adat Minangkabau dan posisi mereka dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun ketegangan antara Islam dan adat telah mewarnai sejarah Minangkabau sejak awal mereka memeluk Islam, hubungan ini telah mengalami berbagai fase ketegangan besar maupun persantaian yang relatif. Dekade terakhir era kepemimpinan Soeharto diwarnai dengan hilangnya perhatian secara umum terhadap adat karena kebangkitan Islam. Kebebasan politis baru dan berbagai kebijakan desentralisasi meningkatkan identifikasi dengan adat bahkan di antara elit-elit perkotaan, dan mendorong Islam untuk lebih ditonjolkan. Gerakan kembali ke surau harus dilihat sebagai suatu usaha untuk menyeimbangkan hubungan antara adat dan Islam.
Pada masa kolonial, adat sebagai sebuah kesatuan politik, sebuah kekuatan yang berada dalam koridor kekuasaan kolonial pada awalnya berarti suatu usaha perlindungan. Para pengusungnya mempunyai perhatian sekurang-kurangnya dalam masalah prinsip untuk melindungi kelompok masyarakat adat yang lemah terhadap masyarakat luar yang kuat, untuk mencegah upaya pemilik modal dalam menguasai tanah-tanah warisan leluhur serta kaum birokrat yang hendak menghancurkan adat istiadat mereka. Namun, setelah kemerdekaan dan kejatuhan demokrasi liberal pada tahun 1959, adat mengalami pergeseran makna. Adat lebih cenderung menjadi sebuah ideologi penguasaan daripada ideologi perlindungan. Sementara hak-hak dan lembaga adat yang riil pada tingkat daerah sengaja dilemahkan oleh legislasi nasional. Pada tingkat nasional, gagasan mengenai kolektivisme berbasiskan adat sebagai sumber kepribadian bangsa Indonesia memberikan sebuah alasan pembenaran dalam pemaksaan akan kepatuhan penduduk. Di penghujung abad ke-XX, roda kembali berputar ke tempat sebelumnya ketika kembali munculnya suara-suara yang memperjuangkan dan membela komunitas lokal terhadap ancaman-ancaman dari luar ataupun dari negara sendiri dengan mengatasnamakan adat.
Kebangkitan ini merupakan inisiatif dari orang-orang luar yang bukanlah orang Indonesia asli. Meskipun demikian, perbedaan utama yang dimunculkan dalam kebangkitan ini adalah politik adat tidak hanya menjadi ideologi perlindungan. Namun lebih dari itu, politik hukum adat
124 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
dapat dimaknai sebagai mobilisasi anggota komunitas adat dalam memperjuangkan berbagai persoalan mereka dengan cara mereka sendiri. Politik adat pada saat sekarang ini mengambil bentuk yang paradoksal, yaitu sebuah konservatisme radikal15 di mana kelompok yang terpinggirkan dan tidak berpunya yang melakukan tuntutan atas keadilan. Tuntutan yang mereka perjuangkan ini bukanlah atas nama keterpinggiran dan ketidakberpunyaan mereka, melainkan atas nama nenek moyang komunitas dan lokalitas mereka.
Orde Baru merupakan rezim penganut paham pembangunan yang otoriter dengan pendekatan tangan besi terhadap pembangunan bangsa. Sementara keragaman budaya Indonesia diakui selaras dengan semboyan bhineka tunggal ika, tidak ada satu pun hak politik yang boleh dibangun di atas perbedaan budaya atau identitas etnis.16 Di Sumatera Barat, sebuah lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau dibentuk pada tahun 1966 untuk membantu melenyapkan paham komunis.17 Di beberapa daerah lain juga dibentuk program-program pembangunan Orde Baru yang terkadang menggunakan istilah-istilah setempat dengan tujuan propaganda.
Kebangkitan adat berpendar dalam suasana kebebasan politik baru era reformasi. Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) yang pertama kali dan ditandai dengan terbentuknya Aliansi Masyarakat Adat nusantara (AMAN) pada Maret 1999 merupakan simbol perubahan radikal yang terjadi di Indonesia.18 Hal utama yang menjadi isu besar yang diangkat oleh komunitas ini adalah sebuah ancaman terbuka19
15 David Henley & Jamie Davidson, “Pendahuluan: Konservatisme Radikal –
Aneka Wajah Politik Adat”, dalam Adat dalam Politik Indonesia, eds. Jamie S. Davidson, David Henley dan Sandra Moniaga (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), 30-31.
16 David Henley & Jamie Davidson, “Pendahuluan: Konservatisme Radikal”, 13.
17 Audrey Kahin, Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatera Barat dan
Politik Indonesia 1926-1998 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), cet-2, 246. 18 Kongres yang diadakan di Jakarta ini sangat mengundang perhatian berbagai
media massa. Kongres ini menampilkan diskusi yang berapi-api tentang represi militer dan hak masyarakat adat untuk menentukan nasib sendiri (right to self-determination). Kongres ini juga menentang pemerintah dengan segenap tuntutan keras, termasuk pengembalian seluruh tanah adat kepada komunitas masyarakat adat dan penghapusan organ-organ pada masa pemerintahan Orde Baru seperti LMD dan LKMD yang kemudian digantikan oleh lembaga adat. G.L. Acciaioli, “Re-empowering the Art of Elders: The Revitalization of Adat Among the To Lindu People of Central Sulawesi and Throughout Contemporary Indonesia”, dalam Beyond Jakarta: Regional Autonomy and
Local Societies in Indonesia, ed. M. Sakai (Adelaide: Crawford House, 2002), 218-219. 19 Ancaman ini dinyatakan oleh lebih dari dua ratus komunitas perwakilan
masyarakat adat dari Aceh sampai Papua. Gerakan ini merapatkan dirinya dengan
FORMALISASI NILAI ADAT MINANGKABAU ... | 125
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
kepada pemerintah bahwa mereka tidak akan mengakui adanya negara apabila negara tidak mengakui eksistensi masyarakat adat di negara ini.20 Pernyataan ini mencerminkan perasaan geram dan frustasi mereka terhadap ketidakmampuan negara dalam menyelesaikan sengketa yang berlarut-larut, bahkan sebagian konflik telah berlangsung puluhan tahun.
Saat-saat menjelang dan sesudah pengunduran diri Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan di awal tahun 1998, politik Indonesia tidak hanya diwarnai oleh gerakan mahasiswa, namun juga gerakan masyarakat di daerah. Isu utama yang dibawa oleh mahasiswa adalah tuntutan pemberantasan kekuatan Orde Baru dan korupsi serta pembentukan pemerintahan yang demokratis. Sementara itu, gerakan masyarakat daerah menuntut kemerdekaan, pemisahan diri dari Indonesia, pemerintahan yang federalistik dan pelaksanaan otonomi daerah seluasnya.21 Pemerintah pada masa reformasi menetapkan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi sebagai tanggapan terhadap tuntutan yang diajukan tersebut.
Era pemerintahan Habibie dan Abdurrahman Wahid, negara mau menjamin setidaknya secara teori, peran-peran politik baru bagi adat pada tingkat daerah. Undang-undang otonomi daerah yang disahkan pada tahun 1999 memberikan kesempatan khusus bagi pembaharuan kelembagaan di tingkat kampung. Pembaharuan ini menekankan betapa pentingnya adat setempat dalam pemerintahan kampung. Pembaharuan ini juga mewajibkan kepada aparatur pemerintah di tingkat kampung untuk mengakui dan menghormati hak, asal-usul, adat dan tradisi kampung.22 Sementara itu, AMAN dan kelompok nasional lain umumnya masih tetap inisiatif desentraliasi dalam pemerintahan Habibie. Hal ini tercermin dalam dorongan terhadap legislasi, baik pada tingkat daerah ataupun pada tataran nasional yang mengakui hak-hak tradisional masyarakat adat yang diawali dengan penetapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. David Bourchier, “Kisah Adat dalam Imajinasi Politik Indonesia dan Kebangkitan Masa Kini”, Adat dalam Politik
Indonesia, eds. Jamie S. Davidson, David Henley dan Sandra Moniaga (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), 137.
20 Sandra Moniaga, “Dari Bumiputera ke Masyarakat Adat”, 301. 21 Pratikno, “Pengelolaan Hubungan Antara Pusat dan Daerah”, Desentralisasi
dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan
Daerah, ed. Syamsuddin Haris (Jakarta: LIPI Press, 2005), 25. 22 Pada tahun yang sama, pemerintah mengadopsi term komunitas adat terpencil
sebagai sitilah resmi yang merujuk pada kelompok-kelompok masyarakat yang sebelumnya dikenal dengan istilah masyarakat terasing. C.R. Duncan, “From Development to Empowerment: Changing Indonesian Government Policies Toward Indigenous Minorities”, Civilizing The Margins: Southeast Asian Government Policies
for Development of Minorities, ed. C.R. Duncan (Ithaca: Cornell University Press, 2004), 90.
126 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
bertahan dengan sikap opsisi mereka. Pada tingkat lokal dan regional, proses desentralisasi memfasilitasi berbagai bentuk akomodasi antara advokasi adat dan negara.
Tujuan utama kebijakan otonomi daerah dapat ditinjau dari dua sisi. Pertama, otonomi daerah merupakan upaya pembebasan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam urusan domestik. Kebijakan otonomi diharapkan memberikan peluang bagi pemerintah pusat untuk mempelajari, memahami dan merespon kecenderungan global. Kedua, dengan adanya desentraliasi kewenangan pemerintah ke daerah, maka daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan. Kreativitas dan prakarsa pemerintahan daerah akan terpacu sehingga kapabilitas dalam penyelesaian masalah domestik semakin kuat. Salah bidang yang menjadi visi utama dalam otonomi daerah adalah daerah diharapkan mampu menciptakan dan memelihara harmonisasi sosial. Pada saat yang sama, otonomi daerah juga diharapkan mampu memelihara nilai-nilai lokal yang bersifat kondusif23 terhadap kemampuan masyarakat dalam merespon dinamika kehidupan di sekitarnya.
Esensi otonomi sesungguhnya adalah proses otonomisasi masyarakat.24 Dalam konteks ini, masyarakatlah yang diberdayakan dalam memahami hak-hak mereka. Rakyat merupakan subjek dalam otonomi daerah. Otonomi diharapkan mampu membuka peluang seluas-luasnya dalam mengembangkan potensi daerah. Untuk menjamin kesuksesan pelaksanaan otonomi daerah, dibutuhkan komitmen yang kuat dan kepemimpinan yang konsisten dari pemerintah pusat. Dari daerah juga diharapkan ada pemerintahan yang demokratis, dewan legislatif yang mampu menjembatani antara aspirasi masyarakat daerah dengan kemampuan pemerintah dan berbagai pendekatan sosial budaya yang secara simultan menyuburkan harmoni dan solidaritas warga.
Ide-ide tentang otonomi daerah dan demokratisasi pada dasarnya sudah mulai diperdebatkan sejak masa-masa awal kemerdekaan. Ide-ide ini dipopulerkan oleh dua orang tokoh yang berpengaruh pada waktu itu, yaitu Mohammad Nasrun dan Mohammad Hatta.25 Mohammad Nasrun26
23 Ryaas Rasyid, “Otonomi Daerah: Latar Belakang dan Masa Depannya”,
Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah, ed. Syamsuddin Haris (Jakarta: LIPI Press, 2005), 11.
24 Jazuli Juwaini, Otonomi Sepenuh Hati: Pokok-pokok Pikiran Untuk
Perbaikan Implementasi Otonomi Daerah (Jakarta: Al-I’tishom, 2007), 14. 25 Gusti Asnan, Memikir Ulang Regionalisme, 146-158 26 Beliau adalah tokoh yang terlibat langsung dalam perdebatan dan
pelaksanaan otonomi daerah. Keseriusan beliau dalam menanggapi otonomi daerah
FORMALISASI NILAI ADAT MINANGKABAU ... | 127
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
adalah Gubernur Sumatera Tengah sewaktu ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948. Nasrun memfokuskan pemikiran tentang konsep otonomi pada daerah terendah. Hal didasarkan pada sebuah argumen bahwa otonomi daerah terendah merupakan sendi masyarakat.27 Sebagai sendi masyarakat, maka ia juga akan menjadi sendi negara. Lebih jauh lagi, beliau berpendapat bahwa pada otonomi daerah terendah inilah kesatuan masyarakat dapat terwujud. Pada tingkatan ini pula dinamika masyarakat dalam berbangsa dan bernegara mempuyai peranan penting karena adanya pertemuan hubungan pemerintah dengan masyarakat. Pemikiran inilah yang mendorong beliau untuk membentuk Panitia Desentralisasi. Beliau menginginkan adanya penyesuaian konsep nagari, marga dan desa yang dimiliki oleh masyarakat untuk dijadikan sebagai daerah otonom pada tingkat terendah. Penyesuaian yang dimaksudkan adalah penyelarasan dengan keinginan negara modern yang memberikan porsi lebih dalam tingkat keaktivan dan kedinamisan masyarakat serta bertindak atas dasar kesamaan hak dan secara demokratis.
Hampir sama dengan pemikiran Nasrun, Mohammad Hatta juga mempunyai beberapa pokok pikiran yang berkaitan dengan konsep otonomi daerah dan demokratisasi.28 Merujuk pada defenisi otonomi yang dimaknai sebagai sebuah hak untuk menjalankan dan mengurus rumah tangga daerah seluas-luasnya, Hatta menyatakan bahwa di dalamnya telah tercakup makna demokrasi.29 Penyerahan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dirinya sendiri memang seharusnya dilakukan dalam sebuah Negara modern dengan tingkat heterogenitas yang tinggi dan wilayah teritorial yang luas. Konsep ini merupakan sebuah proses demokratisasi, karena tanggung jawab juga dibebankan kepada beberapa
terlihat dalam beberapa tulisan beliau seperti; Masalah Sekitar Otonomi (1951), Sendi Negara dan Melaksanakan Otonomi dan Otonomi Daerah Terendah.
27 Mohammad Harun, Daerah Otonomi Tingkat Terbawah (Jakarta: Beringin Trading Company, t.th), 8.
28 Mohammad Hatta mempublikasikan pemikirannya melalui media massa Haluan. Setidaknya pada tahun 1957 ada sekitar 5 tulisan beliau yang dimuat dalam harian tersebut. Beliau mulai banyak menuliskan konsep otonomi daerah setelah beliau mengundurkan diri dari jabatan sebagai Wakil Presiden RI pada November 1956.
29 Secara sosiologis, pemikiran Mohammad Hatta merupakan pertemuan antara tiga unsure budaya yang yang relatif serasi, saling mengisi dan saling melengkapi. Ketiga unsur tersebut adalah adat Minangkabau, ajaran Islam dan pemikiran moern dari Barat. Ketiga unsur ini dalam prosesnya saling terintegrasi. Pemikiran Hatta ini berada dalam bentuk sublimasi yang jernih dan prima yang lebih menekankan penjabaran inti dan hakekat daripada retorika verbalisme. Abdul Rasyid Rahman, Konsepsi Mohammad Hatta tentang Islam dan Demokrasi Sosial (Tesis Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, 1999), 147.
128 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
pihak yang seharusnya. Demokrasi dan tanggung jawab merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan sebagaimana layaknya hubungan antara hak dan kewajiban.
Pemikiran Hatta mengenai otonomi daerah didasarkan pada satu ide pokok bahwa sebuah negara yang demokratis harus memangkas sebanyak mungkin tingkatan yang ada dalam pemerintahannya. Hal ini dikarenakan sebuah pemerintahan dengan banyaknya tingkatan hanya akan membentuk sistem hubungan hierarkis sehingga tidak demokratis lagi. Pemikiran inilah yang melatarbelakangi penetapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Pemikiran Hatta ini juga tercermin ketika beliau menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 1948 melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 1948 tentang Pembagian Sumatera Menjadi Tiga Provinsi.
Sedikit berbeda dengan pemikiran Nasrun, Hatta menempatkan titik berat otonomi pada tingkatan kabupaten. Seiring dengan konsep ini, Hatta mengusulkan untuk menjadikan provinsi sebagai lembaga koordinasi antar kabupaten yang berada dalam lingkungannya. Hal ini berbeda dengan keinginan Nasrun yang meletakkan titik berat otonomi pada tingkatan nagari, marga atau desa. Meskipun demikian, Hatta tetap menginginkan nagari, marga dan desa sebagai daerah otonomi terendah dengan mempertahankan bentuk aslinya, namun titik konsentrasi otonomi tetap berada pada tingkatan kabupaten. Hatta berpendapat bahwa pemikiran ini akan menjaga dan melanjutkan organisme yang sudah lama hidup dalam masyarakat. Pilihan ini sekaligus juga mempertahankan warisan luhur bangsa seperti tradisi demokrasi yang asli serta menjamin kelanjutan praktik gotong royong di tengah masyarakat.
Sejak awal ditetapkan, kebijakan otonomi daerah telah dicurigai oleh berbagai kalangan sebagai sebuah kebijakan yang dapat mengancam integrasi nasional.30 Prasangka ini terlalu berlebihan karena beranjak dari penggunaan paradigma lama yang menyatakan bahwa integrasi nasional hanya bisa dijaga dengan bentuk pemerintahan yang sentralistik. Sementara itu dalam realitas sosial yang sudah terjadi di Indonesia, konsep kepemimpinan yang sentralistik itulah yang menjadi penyebab utama keterpurukan sebagai bangsa. Kalangan ini juga gagal dalam memahami bahwa penjagaan integrasi nasional bukan semata-mata menjadi kewajiban pemerintah pusat, namun juga menjadi kewajiban pemerintah daerah beserta seluruh masyarakat.
30 Ryaas Rasyid, “Otonomi Daerah”, 16.
FORMALISASI NILAI ADAT MINANGKABAU ... | 129
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Salah satu daerah yang cepat menanggapi regulasi otonomi daerah ini adalah masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat.31 Hal ini terlihat dari penetapan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari yang ditetapkan tidak lama setelah otonomi daerah mulai dijalankan di Indonesia. Masyarakat Minangkabau sudah lama mengalami proses individualisasi dan seringkali berasal dari bawah.32 Perubahan ini didukung oleh adanya serangkaian regulasi negara terhadap nagari. Regulasi Negara ini menuntut agar pemerintahan nagari bercorak seragam dan sesuai dengan peraturan yang berskala nasional. Pada dasarnya, klan Minangkabau sudah sejak lama dipersoalkan. Mulai dari abad ke-20, Pemerintah Belanda berulang kali ingin menghilangkan fungsi-fungsi penghulu Minangkabau33 yang berdampak pada perombakan total sistem pemerintahan di daerah Minangkabau. Perombakan total ini berakibat pada hilangnya sendi-sendi pemerintahan yang dilandaskan pada nilai-nilai adat dalam nagari di Minangkabau. Menteri Cremer pada masa itu ingin menghapuskan keberadaan hukum adat melalui rencana undang-undang mengenai pasal 75, 85, 86 dan 109 RR. Alasan utama penghapusan ini dalah dikarenakan hukum adat itu terlalu banyak berbeda dan seringkali tidak mempunyai ketentuan yang jelas. Tujuan penghapusan ini adalah untuk mempermudah pemerintah dan kinerja hakim dalam menyelesaikan dualisme hukum dalam lembaga peradilan.34
Di pihak lain, C. Snouck Hurgronje mengemukakan alasan berbeda dalam upaya kodifikasi hukum adat. Demikian juga dengan kecaman C. Van Vollenhoeven terhadap Pemerintah Belanda yang
31 Franz and Keebet von Benda-Beckmann, “Recentralization and
Decentralization in West Sumatera”, Decentralization and Regional Autonomy in
Indonesia: Implementation and Challenges, eds. Coen J.G. Holtzappel & Martin Ramstedt (Singapore: ISEAS Publishing, 2009), 293.
32 Iskandar Kemal, Pemerintahan Nagari Minangkabau & Perkembangannya:
Tinjauan Tentang Kerapatan Adat (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), ed-2, 13. Dengan ditetapkannya Perda Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari, batas-batas desa digariskan kembali dan komunitas-komunitas desa noe-tradisional dalam batas-batas nagari dimunculkan kembali. Franz & Keebet von Benda-Beckmann, “Identitas-identitas Ambivalen”, 544.
33 Hal ini senada dengan apa yang diungkapan oleh Mr. I.A. Nederburgh bahwa di Indonesia harus diadakan unifikasi hukum. Penjelasan lebih lanjut, lihat dalam C. Van Vollenhoeven, Het Adatrecht van Nederlandsch Indie (Leiden: E.J. Brill, 1933), 13.
34 C. Fasseur, “Dilema Zaman Kolonial: van Vollenhoven dan Perseteruan Antara Hukum Adat dan Hukum Barat di Indonesia”, dalam Adat Dalam Politik
Indonesia, eds. Jamie S. Davidson, David Henley dan Sandra Moniaga (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), 67.
130 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
mengacuhkan keberadaan hukum adat.35 Lebih jauh lagi, Van Vollenhoeven berpendapat bahwa pemerintah adalah penghalang utama dalam kemajuan hukum adat bumi putera. Terhadap hal ini, Van Vollenhoeven berpendapat bahwa persoalannya harus dilihat dari segi kepentingan masyarakat itu sendiri, bukan dari sudut kepentingan politik pemerintahan saja. Usaha van Vollenhoeven ini berhasil. Hal ini terlihat dengan mulai ditinggalkannya upaya unifikasi hukum sejak tahun 1928.36
Idealnya, politik negara bertujuan untuk menjamin terlaksananya kepentingan rakyat. Pemerintahan golongan genelaogis mempunyai kedudukan dalam pemerintahan nagari di Minangkabau, namun juga membuka peluang bagi golongan individu untuk menjadi anggota B.37 Pemerintahan nagari ini dapat berkembang sebagai dasar pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam IGOB dan MIVB.38 Akan tetapi, setelah Perang Dunia II berakhir, kebijakan yang sudah dihapuskan pada masa van Vollenhoeven kembali digunakan. Pemerintahan kolonial yang baru mempertanyakan kembali kegunaan mempertahankan hukum adat. Perdebatan yang masih berlangsung sampai saat ini adalah tentang hukum adat di Indonesia. Secara historis, unifikasi hukum telah didukung sebagai salah satu prasyarat bagi pembangunan nasional pada era Orde Baru. Lebih jauh lagi dinyatakan bahwa sebuah proses pembangunan nasional membutuhkan kesatuan hukum nasional. Sementara itu, pluralisme hukum telah diadvokasikan sebagai kebutuhan sosial39 berupa pengakuan yang tidak terhindarkan terhadap keragaman hukum yang hidup dan dipakai dalam masyarakat Indonesia.
35 Ahmad Baso, Islam Pasca-Kolonial: Perselingkuhan Agama, Kolonialisme
dan Liberalisme (Bandung: Mizan, 2005), 174. Ketidaksetujuan van Vollenhoven terhadap pengacuhan hukum adat terlihat ketika Rochussen menyebutkan bahwa hukum mengikuti dan harus sejalan dengan agama, segala undang-undang untuk bangsa Jawa dan Arab tidak boleh memuat hal yang bertentangan dengan Alquran. Pikiran inilah yang kemudian menjadi dasar terbentuknya teori recptie in complexu. R. Soepomo dan R. Djokosutono, Sejarah Politik Hukum Adat Masa 1848-1928 (Jakarta: Prandya Paramita, 1982), 70-82.
36 Peter Burns, “Adat, Yang Mendahului Semua Hukum”, dalam Adat Dalam
Politik Indonesia, eds. Jamie S. Davidson, David Henley dan Sandra Moniaga (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), 87.
37 Lihat Staatsblad 1918 Nomor 677 pasal 1 ayat (2). 38 Penjelasan lebih lanjut, lihat keterangan yang dimuat dalam Staatsblad 1931
Nomor 307. 39 Daniel Fitzpatrick, “Tanah, Adat dan Negara di Indonesia Pasca-Soeharto:
Persepktif Sorang Ahli Hukum Asing”, Adat dalam Politik Indonesia, eds. Jamie S. Davidson, David Henley dan Sandra Moniaga (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), 143.
FORMALISASI NILAI ADAT MINANGKABAU ... | 131
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Perdebatan mengenai politik hukum adat yang terjadi pada masa kolonialisasi Belanda ternyata terulang kembali pada masa awal kemerdekaan. Hal ini terlihat dari beberapa pemikiran yang dimunculkan oleh pengikut van Vollenhoeven dan Ter Haar seperti Soepomo. Soepomo menyatakan bahwa tidak seorang pun yang mempunyai pemikiran akan membubarkan persekutuan famili di Minangkabau. Hal ini dikarenakan mustahil untuk dapat terjadi. Beberapa tokoh40 juga menyatakan bahwa pelaksanaan adat pada era kemerdekaan membutuhkan pembaharuan agar tidak ketinggalan dan mengurangi semangat kemerdekaan. Kondisi ini sangat mungkin untuk berlaku di Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh Snouck Hurgronje41 bahwa adat berdalih dengan angkatan-angkatan yang susul menyusul dan tidak pernah berhenti.
Di tengah keragaman budaya dan etnis Indonesia yang luar biasa, Sumatera Barat sering dipandang sebagai daerah yang relatif homogen dalam budaya dan adat. Mayoritas penduduk di daerah ini berasal dari etnis Minangkabau yang beragama Islam dengan identitas etnis yang kuat.42 Akan tetapi, hal ini sama sekali tidak berarti bahwa di daerah tersebut tidak terdapat perbedaan tentang peran adat dalam kehidupan sehari-hari dan khususnya dalam hal hubungan antara Islam dan adat.
Di dalam masyarakat Minangkabau, adat dan Islam memiliki dimensi yang tampaknya saling berseberangan dan membutuhkan rekonsiliasi ideologis dan sosial.43 Meskipun pada saat sekarang banyak orang yang secara sungguh-sungguh untuk menunjukkan bahwa hubungan antara keduanya tidak lagi menjadi masalah, dalam kenyataannya tidak selalu demikian. Hubungan adat dan Islam di Minangkabau mempunyai sejarah panjang, perdebatan dan perjuangan yang sengit dan sangat menentukan mana yang akan tetap bertahan.
40 Hal ini terlihat dari pandangan yang disampaikan oleh M. Nasrun. Beliau
adalah tokoh yang berasal dari keturunan Bundo Kanduang. M. Nasrun menyatakan bahwa masyarakat yang ber-sendi paruik ini sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan semangat kemerdekaan. Demikian juga dengan apa yang diungkapkan oleh M. Yamin. Beliau berpendapat bahwa dalam praktik negara berdasarkan IGOB, NIVB sudah tidak diacuhkan lagi. Hal ini dengan sendirinya tidak dapat diterima oleh masyarakat untuk dijalankan sebagai peraturan hukum menurut kepribadian Indonesia. Iskandar Kemal, Pemerintahan Nagari Minangkabau, 15-16.
41 C. Snouck Hurgronje, Aceh, 353. 42 Renske Biezeveld, “Ragam Peran Adat”, 222. 43 Franz and Keebet von Benda-Beckmann, “Adat and Religion in
Minangkabau and Ambon”, dalam Time Past, Time Present, Time Future: Perspectives
on Indonesian Cultures, Essay in Honour of Prefessor P.E. de Josselin de Jong, eds. H.J.M. Claessen dan D.S. Moyer (Foris: Dordrecht, 1988), 198.
132 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Secara umum, terdapat dua pandangan yang relevan dan masih bertahan sampai saat ini.44 Pertama, bahwa adat dilandasi dengan iman seperti halnya yang dinyatakan dalam Alquran. Menurut pandangan ini, Islam lebih diutamakan daripada adat. Kedua, pandangan yang menyatakan bahwa adat dilandasi iman dan iman pun dilandasi adat, sehingga kedudukan di antara keduanya saling menguatkan.
Dekadensi moral dan disorientasi serta kemelut budaya saat ini sedang melanda segenap wilayah di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Kondisi ini harus diakhiri dengan cara mengembalikan jati diri. Hal inilah yang menjadi titik tolak kemunculan semangat babaliak ka nagari,
babaliak ka surau (kembali ke nagari, kembali ke surau) di Minangkabau. Semangat tersebut secara sederhana dimaknai dengan mengembalikan pegangan hidup ke kondisi semula. Patokan awal yang dipakai dalam kehidupan masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat adalah konsep “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, syarak mangato, adat
mamakai” (adat bersendikan syarak, syarak bersendikan Kitabullah, syarak mengatakan, adat melaksanakan).45 Konsep inilah yang kemudian dikenal dengan ABSSBK. Melalui pegangan hidup ABSSBK ini masyarakat Minangkabau menyikapi diri dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan.
Eksistensi hak otonomi secara luas bagi daerah pasca Orde Baru memberikan harapan kepada para politisi dan pemuka masyarakat Minangkabau untuk mengukuhkan kembali jati diri Minangkabau dalam kehidupan masyarakat Sumatera Barat. Menyelami dan menemukan jati diri merupakan hakikat ajaran dan pandangan hidup (weltanschauung) dan memakaikannya kembali. Antara nagari, surau dan pegangan hidup ABSSBK terdapat benang merah yang saling mempertemukan serta menjadikan m(inangkabau) itu seperti M(inangkabau) seharusnya.46 Konsep nagari, surau dan pegangan hidup ABSSBK bisa diartikan secara riil dan abstrak. Masing-masing komponen telah mengalami banyak perubahan dan penyesuaian dalam proses panjang sejarahnya. Berbagai perubahan dan penyesuaian tersebut tidaklah mempengaruhi inti, nilai-nilai esensi dan semangat yang ada di dalamnya. Nagari dan surau merupakan wadah sosio-kultural yang sifatnya material dan spiritual. Sementara ABSSBK merupakan pandangan hidup yang memberikan isi
44 Renske Biezeveld, “Ragam Peran Adat “, 225. 45 Mochtar Naim, “Dengan ABSSBK Kembali ke Jati Diri”, Minangkabau yang
Gelisah: Mencari Strategi Sosialisasi, Pewarisan, Adat dan Budaya Minangkabau untuk
Generasi Muda, eds. Buchari Alma, et. all. (Bandung: Lubuk Agung, 2004), 43. 46 Mochtar Naim, “Dengan ABSSBK”, 43. Maksudnya adalah upaya untuk
membentuk masyarakat Minangkabau yang seutuhnya.
FORMALISASI NILAI ADAT MINANGKABAU ... | 133
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
dan mempertemukan antara kehidupan yang bersifat material dan spiritual tersebut.
Pemerintahan era reformasi dengan konsep otonomi daerah memberikan kebebasan kepada daerah untuk melakukan revitalisasi nilai-nilai tradisional setiap daerah. Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat melalui dewan legislatif memanfaatkan kondisi ini dengan baik.47 Merujuk pada konsep integrasi nilai-nilai adat dan ajaran Islam48 yang menjadi pegangan hidup masyarakat Minangkabau, upaya revitalisasi dan formalisasi ini dapat ditinjau dalam Perda Nomor 9 Tahun 2000 jo. Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari.
Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan keleluasaan yang besar (zelfstandingheid)49 kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Amandemen Undang-undang Dasar 1945 juga memberikan peluang yuridis bagi daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan berbagai peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.50 Kewenangan luas tersebut haruslah dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Kesejahteraan dan keadilan sosial bersama ini diwujudkan dalam bentuk produk perundang-undangan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Usaha melahirkan peraturan perundang-undangan yang responsif dan populistik bukan hanya menjadi tugas bagi pemerintah pusat, namun juga menjadi tugas bagi pemerintah di tingkat daerah. Peraturan daerah
47 Sjafri Sairin, “Minangkabau yang Gelisah”, Minangkabau yang Gelisah:
Mencari Strategi Sosialisasi, Pewarisan, Adat dan Budaya Minangkabau untuk Generasi Muda, eds. Buchari Alma, et. all. (Bandung: Lubuk Agung, 2004), 55.
48 Warna Minangkabau dinyatakan dalam adagium adat basandi syarak, syarak
basandi Kitabullah (ABSSBK). Hal ini menunjukkan adanya perpaduan (fusi) antara kebiasaan pra-Islam dengan Islam yang datang ke Minangkabau. Pemurnian pengamalan Islam dalam masyarakat Minangkabau telah dilakukan sebanyak 2 kali. Pertama adalah ketika masa gerakan paderi. Kedua adalah pemurnian melalui pendidikan formal ataupun pengajian yang dilakukan di surau-surau di awal abad ke-XX. Hal ini telah memperdalam pengaruh ajaran Islam ke dalam adat dan budaya Minangkabau. Dengan adanya pembaharuan tersebut, maka hal-hal yang bertentangan dan tidak sesuai dengan ajaran Islam mulai ditinggalkan. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa pada batas tertentu, budaya Minangkabau merupakan budaya Islam yang mendapat warna setempat. Azmi, “Pelestarian Adat”, 77-78.
49 Keleluasaan yang diberikan bukanlah suatu bentuk kebebasan satuan pemerintahan yang merdeka (onafhankelijkheid). Jazim Hamidi dan Kemilau Mutik, Legislative Drafting: Seri Naskah Akademik Pembentukan Perda (Yogyakarta: Total Media, 2011), 61.
50 Jazim Hamidi dan Kemilau Mutik, Legislative Drafting, 3.
134 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
dibentuk oleh DPRD yang dibahas bersama dengan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama. Proses pembahasan dan persetujuan ini dibahas bersama di DPRD. Pembentukan peraturan daerah diawali dengan proses penyusunan rancangan perda. Proses ini sangat menentukan kualitas perda yang dibentuk. Proses ini membutuhkan kearifan dan partisipasi bersama antara pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat.
Peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang di dalam pokok pikiran konsiderannya memuat unsur filosofis, yuridis dan sosiologis. Hal ini sangat jauh berbeda dengan peraturan pemerintah yang hanya memuat satu pokok pikiran dengan merujuk kepada pasal yang mengatur keharusan untuk membuatnya. Secara hierarkis, peraturan daerah merupakan peraturan perudang-undangan yang terintegrasi dengan peraturan perudang-undangan yang berada di atasnya dan mempunyai daya sentuh yang kuat dalam kehidupan bermasyarakat.
Idealnya, sebuah proses pembentukan undang-undang diawali dengan adanya naskah akademik.51 Naskah akademik merupakan pokok pikiran awal (first draft) dalam upaya perancangan suatu peraturan perudang-undangan. Demikian juga halnya dengan peraturan daerah. Peraturan daerah juga diawali dengan naskah akademik guna memudahkan para perancang untuk membuat perumusan RUU atau Raperda yang sedang disiapkan. Naskah akademik memuat gagasan-gagasan kongkrit yang langsung dapat dioperasionalkan untuk merumuskan norma-norma hukum sebagai materi peraturan perundang-
51 Beberapa ahli mengemukakan berbagai defenisi tentang naskah akademik.
Mohammad Hasan Wargakusumah menyatakan bahwa naskah akademik merupakan naskah yang memuat gagasan-gagasan pengaturan suatu materi hukum yang telah ditinjau dari berbagai aspek, dilengkapi dengan kerangka referensi yang memuat urgensi konsepsi, landasan dan prinsip-prinsip yang digunakan serta pemikiran tentang norma-norma secara alternatif disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis. Sunaryati Hartono menyatakan bahwa naskah akademik merupakan naskah yang memuat gagasan-gagasan pengaturan suatu materi perundang-undangan (materi hukum) di bidang tertentu yang sudah ditinjau secara sistemik, holistik dan futuristik dari berbagai aspek ilmu dan dilengkapi dengan referensi yang memuat urgensi, konsepsi, landasan dan prinsip-prinsip yang digunakan serta pemikiran tentang norma-normanya secara alternatif yang disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis. Penjelasan lebih lanjut lihat Jazim Hamidi dan Kemilau Mutik, Legislative Drafting, 35-42. Penggunaan istilah naskah akademik peraturan perundang-undangan secara baku dimulai sejak tahun 1994 melalui Keputusan Kepala badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Nomor G.159.PR.09.10 Tahun 1994 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan.
FORMALISASI NILAI ADAT MINANGKABAU ... | 135
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
undangan yang didasarkan pada hasil pengkajian, penelitian ilmiah, analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sumatera Barat merupakan provinsi pertama yang melakukan restrukturisasi administrasinya. Skala wilayah dan administrasi pemerintahan desa ditransformasikan dari administrasi desa yang lebih kecil dan murni ke bentuk pemerintahan nagari. Nagari merupakan bagian yang paling penting dari organisasi politik Minangkabau era pra-kolonial.52 Nagari merupakan unit-unit politis territorial yang sangat otonom. Kepemimpinan, afiliasi kelompok dan hubungan-hubungan property didasarkan atas struktur matrilineal. Nagari merupakan unit pemerintahan daerah terendah pada era kolonial53 dan setelah kemerdekaan.
Nagari dalam tradisi masyarakat Minangkabau adalah identitas (icon) kultural dari sebuah tatanan masyarakat yang demokratis. Dalam nagari terkandung sistem yang memenuhi persyaratan embrional sebuah sistem negara.54 Nagari yang terdiri dari suku-suku dalam artian miniatur dan merupakan sebuah republik kecil yang bersifat self continued, otonom dan mampu membenahi diri sendiri. Sebagai sebuah lembaga, nagari tidak hanya dipahami sebagai sebuah kualitas teritorial, namun juga dipahami dengan kualitas genealogis. Orang Minangkabau hidup dalam lingkaran nagari. Sejauh apapun ia pergi merantau, ia tetap mempunyai nagari tempatnya kembali. Nagari merupakan sumber identitas dan sekaligus menjadi sumber rujukan dan aspirasinya. Masyarakat Minangkabau hidup dalam tatanan sosial yang yang baku dan mempunyai format yang jelas.
Pada sisi lain, Gusti Asnan mengemukakan sebuah pandangan yang berbeda terhadap masyarakat Minangkabau dan nagari. Sebagian masyarakat Minangkabau beranggapan bahwa nagari merupakan produk asli masyarakat Minangkabau. Dalam artian lain, nagari merupakan mahakarya masyarakat Mianangkabau semata dan keberadaannya hanya karena masyarakat Minangkabau. Nagari merupakan sebuah trade mark, namun telah menjadi simbol dan perwujudan sebagai tatanan sistem
52 Franz & Keebet von Benda-Beckmann, “Recentralization and
Decentralization in West Sumatera”, 293. 53 Pemerintah Kolonial mendasarkan sistem pemerintahan tidak langsung
mereka pada struktur pemerintahan nagari selaku desa adat di Minangkabau, sementara menindas struktur-struktur Islami. Franz & Keebet von Benda-Beckmann, “Identitas-identitas Ambivalen”, 545.
54 Bustanul Arifin, et. all., Manajemen Suku, eds. Marwan & Bustanul Arifin (Jakarta: Solok Saiyo Sakato Press, 2012), 23.
136 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
sosial, politik dan budaya masyarakat Minangkabau.55 Pandangan ini muncul dari analisis sejarah pembentukan nagari pada masa awal Minangkabau. Secara historis,56 nagari merupakan unit teritorial tertua bersifat otonom yang dikenal dalam masyarakat Minangkabau.
Beberapa literatur yang mengkaji teori-teori nagari tradisional menyatakan bahwa nagari, selain memerankan dirinya sebagai suatu kesatuan yang merdeka, mirip dengan republik kecil yang otonom, juga ada beberapa wilayah yang tergabung dalam entitas geografis dan politik di bawah kekuasaan Raja Pagaruyung. Posisinya pada tingkat supra-nagari kurang lebih sama dengan fungsi dan pola penghulu di tingkat nagari.57 Dua raja yang menjadi pendampingnya adalah Rajo Adat (yang berwenang dalam masalah adat) dan Rajo Ibadat (yang berwenenang dalam masalah agama Islam).58 Beberapa pendapat59 seperti yang dikutip oleh Elizabeth E. Graves menyatakan bahwa kedua divisi pemerintahan ini mewakili dua subdivisi geografis utama dalam kerajaan, atau keduanya tidak lebih dari simbol-simbol kosmologi aturan alam Minangkabau.
Nagari merupakan lembaga pemerintahan dan dan sekaligus juga merupakan lembaga kesatuan sosial utama yang dominan. Sebagai sebuah kesatuan masyarakat otonom, nagari merupakan sebuah republik mini dengan batasan teritorial yang jelas. Nagari dengan sistem pemerintahan sendiri mempunyai adat sendiri yang mengatur tata kehidupan masyarakatnya. Nagari merupakan daerah dalam lingkungan konfederasi kultural Minangkabau yang berhak mengurus dirinya sendiri. Dalam persepktif lain dapat disimpulkan bahwa lembaga nagari berfungsi sebagai lembaga adat dan pemerintahan yang saling berhubungan dalam bentuk kesatuan yang integral. Nagari dalam sistem pemerintahannya tidak hanya terkait dengan unsur legislatif, eksekutif dan yudikatif semata, namun juga merupakan kesatuan holistik bagi perangkat tatanan sosial budaya lainnya. Ikatan yang dibentuk dalam sebuah nagari tidak hanya bersifat primodial konsanguinal (ikatan kedaerahan dan kekerabatan adat), namun juga bersifat struktural fungsional dalam artian
55 Gusti Asnan, Nagari Pada Masa Kolonial (Padang: Lentera 21, tth), 33. 56 Imran Manan, Nagari Pra Kolonial (Padang: Lentera 21, 2003), 22. 57 Elizabeth E. Graves, Asal Usul Elite Minangkabau, 36. 58 P.E. de Josselin de Jong, Minangkabau and Negeri Sembilan: Socio-Political
Structure in Indonesia (Jakarta: Bharatara, 1960), 13-14. 59 William Marsden, The History of Sumatera (London: J. McCerrey, 1811),
282-283, lihat juga dalam P.E. de Josselin de Jong, Minangkabau and Negeri Sembilan,
107-111.
FORMALISASI NILAI ADAT MINANGKABAU ... | 137
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
teritorial pemerintahan yang efektif. Secara horizontal, antar sesama mempunyai ikatan emosional dan bukan struktural fungsional.
Nagari mempunyai sistem dan struktur yang bersifat otonom dan dikelola secara demokratis serta mengenal sistem hierarki yang berjenjang naik dan bertangga turun. Sebuah nagari diatur dengan sistem musyawarah dari wakil-wakil yang duduk di Kerapatan Adat Nagari, Badan Perwakilan Rakyat Nagari dan lain sebagainya. Perwakilan nagari pada dasarnya merepresentasikan unsur-unsur yang ada dalam masyarakat. Konsep TTS (Tungku nan Tigo Sajarangan) dalam sebuah sistem kepemimpinan egaliter masyarakat Minangkabau sangat unik. Dalam konsep kepemimpinan seperti ini, kekuasaan tidak hanya dipegang oleh satu orang saja. Kekuasaan dalam nagari di Minangkabau dibagi secara proporsional dan fungsional di antara ketiga unsur tripartite tersebut, yaitu ninik mamak, alim ulama dan cadiak pandai (cendikiawan).
Bagi masyarakat Sumatera Barat, term nagari sudah membumi dan tidak dapat dipisahkan antara primodialisme dengan nilai-nilai berbangsa, antara struktur sosial dan administrasi negara, antara adat dan pemerintahan, antara kolektivitas kesukuan dan pembangunan.60 Nagari merupakan sebuah kesatuan sosial politik masyarakat Minangkabau yang paling tepat digambarkan sebagai sebuah desa atau himpunan beberapa desa dan pemukiman. Seringkali nagari dipandang sebagai sebuah republik desa yang otonom,61 meskipun kandungan dan cakupan otonominya masih diperdebatkan.62 Penduduk sebuah nagari terbagi dalam garis keturunan ibu (matrilineal).
Nagari merupakan inti dari sistem kekerabatan matrilineal yang diapaki oleh masyarakat hukum adat Minangkabau. Nagari yang tidak lain merupakan bentuk perkampungan atau unit teritorial lengkap dengan aparat politik, adat dan hukumnya sendiri, diakui sebagai organisasi pemukiman masyarakat Minangkabau yang diakui oleh adat. Meskipun
60 Nofil Ardi, “Pemerintahan Nagari dan Kelembagaan Adat Minangkabau”,
dalam Minangkabau yang Gelisah: Mencari Strategi Sosialisasi Pewarisan Adat dan
Budaya Minangkabau untuk Generasi Muda, eds. Buchari Alma, et. all. (Bandung: Lubuk Agung, 2004), 148.
61 Nagari pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan sebuah negara yang mempunyai perangkat pemerintahan yang dibutuhkan, seperti lembaga legislatif, lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif. Kondisi inilah yang mendorong peneliti Barat menjulukinya dengan sebutan petits republiques (republik-republik kecil). Mochtar Naim, “Dengan ABSSBK”, 45. Bandingkan dengan penjelasan Elizabeth E. Graves, Asal Usul Elite Minangkabau, 37.
62 Renske Biezeveld, “Ragam Peran Adat”, 223.
138 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
semua nagari mempunyai cita-cita ideal dan prinsip-prinsip adat yang umum, masing-masing nagari mempunyai batasan yang jelas dan teritorial satelitnya. Berdasarkan komponen-kompenan dan karakteristik yang dimiliki oleh sebuah nagari, maka setiap nagari merupakan entitas politik yang independen.63 Dengan kurangnya kekuasaan politik yang tersentralisasi di alam Minangkabau, nagari dengan otonominya yang kuat sering kali dikarakterisasikan sebagai republik desa.
Nagari atau yang sering juga disebut dengan kenagarian merupakan sebuah negara mini yang berdiri secara otonom. Setiap nagari mempunyai wilayah dan sistem pemerintahan yang jelas dan lengkap, mempunyai tatanan adat sendiri yang dikenal dengan adat nan taradat.64 Kepemilikan adat nan taradat ini menjadi sebuah identitas pembeda antara satu nagari dengan nagari lainnya. Sebuah nagari juga mempunyai dialek bahasa yang khas serta mempunyai tanah ulayat sebagai sumber finansial tersendiri dengan batasan-batasan yang jelas.
Ditinjau dari proses pembentukan sebuah nagari di Minangkabau, secara sederhana dapat diilustrasikan sebagai berikut : 1. Nagari merupakan himpunan dari beberapa koto,65 dimana setiap koto
merupakan himpunan dari orang sesuku dengan satu pucuk pimpinan yang disebut dengan penghulu;
2. Koto itu sendiri merupakan himpunan dari beberapa dusun. Dusun merupakan himpunan dari beberapa jurai kaum yang terbentuk dari beberapa taratak. Taratak adalah himpunan dari sekelompok orang dalam ikatan saparuik
66 (keluarga seibu dan saudara).
63 Azyumardi Azra, Surau, 38. 64 Dalam persepktif lembaga adat, nagari merupakan sebuah kesatuan
masyarakat dan hukum adat yang dikenal dalam filosofi nagari bagapa undang, adat
salingka nagari (sebuah nagari dipagari dengan adanya undang-undang, undang-undang itu hanya berlaku dalam kawasan nagari tersebut). Lembaga adat disusun berdasarkan prinsip-prinsip kekerabatan matrilineal dan teritorial yang sudah dilaksanakan sejak masa sebelum kemerdekaan.
65 Koto merupakan cikal bakal berdirinya sebuah nagari. Tidak ada laporan resmi terkait jumlah nagari asli (nagari adat) sebelum masa Pemerintahan Belanda. Ketiadaan laporan ini berlanjut hingga masa tanam paksa kopi dipraktekkan hingga berakibat pada adanya penambahan nagari-nagari. Bustanul Arifin, et. all., Manajemen
Suku, 27. 66 Penggunaan preposisi sa- yang dipakaikan dalam kata benda dalam bahasa
Minangkabau berarti orang dari ... atau kelompok dari sebuah .... Misalnya sa-paruik, artinya adalah orang-orang yang berasal dari saru perut (rahim). Azyumardi Azra, Surau,
56.
FORMALISASI NILAI ADAT MINANGKABAU ... | 139
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Ada beberapa persyaratan67 yang harus dipenuhi untuk mewujudkan sebuah nagari. Sebuah nagari harus terdiri dari 4 suku yang menjadi penduduknya, mempunyai jalan raya sebagai saranan komunikasi dan transportasi, mempunyai pasar sebagai sarana distribusi, mempunyai sebuah balai sebagai sarana demokrasi dan pemerintahan, mempunyai sebuah mesjid sebagai pusat pembinaan rohani dan kehidupan beragama, mempunyai gelanggang sebagai sarana berolah raga serta mempunyai sarana air bersih untuk warganya. Tidak hanya persyaratan tersebut, setiap nagari mempunyai hak dan kewajiban untuk membentuk sebuah adat nan taradat. Adat nan taradat merupakan hukum dan serangkaian peraturan yang hanya berlaku untuk nagari tersebut. Pembentukan peraturan berskala regional ini tidak boleh menyalahi dan keluar dari dasar falsafah Minangkabau itu sendiri.68
Terbentuknya sebuah nagari baru dalam masa perkembangan Minangkabau diawali dengan pindahnya satu keluarga dengan membuka lahan ke daerah ulayat milik nagari tempat mereka berasal. Biasanya daerah ini masih berupa hutan belukar yang berada di daerah perbukitan atau dataran rendah padang alang-alang yang jauh dari pemukiman semula. Di daerah ini, mereka membuka lahan dalam bentuk ladang atau sawah apabila ada sumber mata air. Kemudian mendirikan tempat bermalam ala kadarnya berupa gubuk yang sangat sederhana. Daerah baru ini disebut dengan taratak yang dihuni oleh para petani yang terpencar dan berjauhan dan pada umumnya belum membawa serta istri bersama mereka. Hubungan antar sesama petani tersebut hampir tidak ada, kalaupun ada hanya dalam bentuk yang sangat sederhana.69
Kondisi tanah ulayat tempat taratak tersebut tidak semuanya baik, karena ada yang subur dan ada juga yang tandus. Jika daerah yang mereka tempati tersebut subur, maka mereka akan mengembangkan tanah garapannya. Sebaliknya, jika tanah garapan tersebut tidak subur, mereka hanya menggarapnya untuk satu kali panen saja. Kawasan taratak yang subur akan terus berkembang dan menjadi pemukiman. Semakin padatnya
67 Dalam tambo Minangkabau dijelaskan bahwa ada beberapa syarat
terbentuknya sebuah nagari, “nagari ba ampek suku, dalam suku babuah paruik; dalam
paruik ado ba jurai, dalam jurai ba pariuak; cupak salingka batuang, adat salingka
nagari; ba labuah nan golong, ba pasa nan rami; ba balai ba musajik, ba galanggang, ba tapian tampek mandi”. Julius Dt. Malako nan Putiah, Mambangkik Batang Tarandam
Dalam Upaya Mewariskan dan Melestarikan Adat Minangkabau Menghadapi
Modernisasi Kehidupan Bangsa (Bandung: Citra Umbara, 2007), 161. 68 Amir Sjarifoedin, Minangkabau: Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain Sampai
Tuanku Imam Bonjol (Jakarta: Gria Media Prima, 2011), 68. 69 Amir Sjarifoedin, Minangkabau, 138-139.
140 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
pemukiman pada taratak tersebut akan meningkatkan intensitas pergaulan dan komunikasi antar penghuninya. Hal ini memicu terbentuknya berbagai kegiatan penduduk setempat, seperti mulai dibentuknya gelanggang pencak silat, kesenian talempong dan lain sebagainya.
Apabila diperhatikan dari sudut pandang sejarah, pertumbuhan dan perkembangan pemerintahan nagari mengalami masa pasang surut karena dipengaruhi oleh kondisi politik pada beberapa periode yang dilalui. Pada masa pra-kolonial, kehidupan nagari sepenuhnya dikendalikan oleh adat.70 Teritorial nagari pada dasarnya terdiri dari hutan tinggi dan hutan rendah. Hutan tinggi merupakan wilayah nagari yang dilindungi. Sedangkan hutan rendah merupakan sawah, ladang, kebun, tanah perumahan serta pekarangan dan semua tanah yang sudah diolah yang berfungsi sebagai dana cadangan, baik bagi nagari maupun bagi anak kemenakan dalam suku.
Pada dasarnya, struktur masyarakat nagari di Minangkabau disusun berdasarkan prinsip-prinsip matrilineal. Apabila dianalisis dari sisi antropologis, maka seharusnya yang mendiami sebuah nagari adalah kelompok kekerabatan yang terdiri dari suku (clan), kaum (lineage) dan paruik (sub-lineage).71 Setiap orang dalam nagari merupakan anggota dari salah satu kelompok matrilineal dalam nagari tersebut. Dalam artian lain, orang tersebut harus menjadi kemenakan dari salah seorang penghulu yang bersangkutan.
Kehadiran pemerintah kolonial mengakibatkan terdegradasinya pamor dan kedudukan penghulu. Sebelum terjadinya Perang Paderi pada tahun 1821, Sumatera Barat berada dalam kesatuan luhak dan rantau yang terdiri dari nagari-nagari yang mempunyai kebebasan secara adat. Namun setelah kedatangan Belanda ke Indonesia, Pemerintah Kolonial secara perlahan dan sistematis mulai mengadakan pendekatan dengan berpedoman pada Regering Reglement (RR) tahun 1854 (Staatsblad Nomor 129 Tahun 1854). Pada Perjanjian Plakat Panjang tahun 1833, Belanda mengakui keberadaan nagari dan berjanji tidak akan ikut campur dalam otonomi nagari. Secara politik, kekuasaan Belanda memberikan kebebasan pemerintah nagari untuk diatur berdasarkan adat yang berlaku. Kondisi ini dipertegas dengan adanya Ordansi 27 September 1918.
70 Keebet von Benda-Beckman, Goyahnya Tangga Menuju Mufakat (Jakarta:
Grasindo, 2000), 67. 71 Silahkan bandingkan beberapa literatur, seperti : Imran Manan, Nagari Pra
Kolonial, 7., Mochtar Naim, Merantau, 18-19., dan A. Rivai Yogi, Sastra Minang (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, tth), 23-24.
FORMALISASI NILAI ADAT MINANGKABAU ... | 141
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Berdasarkan catatan sejarah, dengan ditetapkannya Staatsblad 1874 Nomor 94b pada tanggal 1 November 1874, Pemerintah Hindia Belanda menghapuskan hak kekuasaan penghulu dalam memutus perkara yang terjadi dalam lingkungan nagari. Kompetensi ini beralih kepada hakim Gubernemen Belanda yang dikepalai oleh hakim dari Belanda. Meskipun demikian, nagari-nagari tetap diberikan pengakuan secara sah dengan adanya Inladsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten (IGOB) sebagaimana yang dimuat dalam Staatsblad 1938 Nomor 490.72 Apabila dikaji lebih mendalam, pada dasarnya kedudukan IGOB tidaklah bertujuan untuk mempertahankan atau memperkuat otonomi yang sudah dimiliki oleh nagari. Sebaliknya, IGOB bertujuan untuk memberikan peluang kepada Pemerintah Belanda untuk mencampuri urusan pemerintahan nagari.73 Menariknya, sebagai upaya tindak lanjut dari RR 1854 Nomor 129, maka Pemerintah Hindia Belanda menetapkan Inlandsche Gemente Ordantie (Staatsblad Nomor 321 Tahun 1903) dan dilanjutkan dengan Staatsblad Nomor 667 Tahun 1918. Merujuk pada kedua ordansi tersebut, maka susunan pemerintahan tertata dalam hierarki sebagai berikut.
1. Provinsi, misalnya Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh Gubernur. Beberapa gewest (seperti Gewest Sumatera Barat Tapanuli) dihapus dan digabungkan menjadi provinsi;
2. Residentie atau keresidenan, misalnya Keresidenan Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Residen. Keresidenan Padang Darat (Padangsche Bovenlanden) dan Padang Laut (Padang Benedenlanden) dihapus dan digabungkan menjadi satu keresidenan yakni Keresidenan Sumatera Barat;
3. Afdeling, dipimpin oleh Asisten Residen alias Tuan Luhak ala Minangkabau;
72 Pada tahun 1848, Belanda mengatur pemerintahan nagari yang disesuaikan
dengan kepentingan pemerintahan jajahan. Institusi yang didirikan adalah Tuanku Laras yang merupakan koordinator beberapa nagari terkait pengumpulan pajak dan pelaksanaan tanam paksa. Pemerintahan Tuanku Laras ini berakhir pada tahun 1917 dan diganti dengan Pemerintahan Belanda pada tanggal 27 September 1918 sebagaimana yang dimuat dalam lembaran Negara Nomor 667. Setelah dilakukan perubahan dan penambahan dalam regulasinya, kemudian ditetapkanlah IGOB pada tahun 1938.
73 Salah satu bentuk campur tangan Pemerintah Hindia Belanda dalam otonomi nagari adalah dalam hal pemilihan keanggotaan kerapatan Nagari. Susunan keanggotaan Kerapatan Nagari terdiri dari penghulu bajinih dan penghulu basurek. Penghulu bajinih merupakan penghulu yang diangkat berdasarkan pilihan masyarakat adat. Sedangkan penghulu basurek merupakan penghulu yang keanggotaannya ditunjuk dan disahkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Nofil Ardi, “Pemerintahan Nagari”, 150-151.
142 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
4. Onder Afdeling, dipimpin oleh kontrolir alias Tuan Kumandua ala Minangkabau;
5. District, dipimpin oleh Demang alias Wedana yang memimpin wilayah kewedanaan;
6. Onder District, dipimpin oleh Asisten Demang atau Asisten Wedana atau Camat yang memimpin wilayah kecamatan, dan;
7. Nagari, dipimpin oleh Kepala Nagari atau Angku Palo. Kondisi ini sedikit berbeda dengan masa pendudukan Jepang.
Pada masa penjajahan Jepang, ada sebuah regulasi yang bertujuan untuk menghormati aturan adat dan hubungan nagari. Ketentuan tersebut ditetapkan dalam Osamu Seirei Nomor 7 tahun 1944. Pada masa ini, Pemerintahan Nagari di Minangkabau tetap berjalan sebagaimana biasanya asalkan tidak bertentangan dengan kepentingan militer Jepang. Kondisi ini tetap bertahan hingga masa kemerdekaan Indonesia.
Sedari semula, pemerintah kolonial telah mempengaruhi distribusi kekuasaan dan hak-hak kepemilikan dalam kampung secara signifikan. Periode tanam paksa kopi (1848-1908), liberalisme dan kemudian pada masa kemerdekaan yang semuanya membutuhkan koseptualiasi yang berbeda mengenai hak kepemilikan yang akan melayani kepentingan pemerintah. Hak kepemilikan masyarakat adat diinterpretasikan kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan serta dimanipulasi untuk tujuan berbagai rezim ini. Meskipun intensitas campur tangan dari pemerintahan eksternal berbeda-beda pada serangkaian periode tersebut, namun masih mempunyai tujuan yang sama, yakni membentuk nagari menjadi sebuah kendaraan untuk menerapkan berbagai kebijakan yang diinisiasi dari pusat. Meskipun demikian, nagari telah belajar mempertahankan sebagian besar otonominya secara administratif, ekonomi dan budaya,74 meskipun ukuran tingkat keberhasilan ini berbeda-beda pada tiap nagari.
Pemerintah kolonial Belanda melalui Plakat Panjang pada tahun 1833 telah berjanji untuk tidak akan ikut campur dalam lembaga-lembaga adat, namun kenyataannya mereka melanggar perjanjian tersebut. Hal ini terlihat dari adanya kebijakan terkait masalah tanam paksa kopi (coffiestelsel). Melalui kebijakan ini Pemerintah Hindia Belanda menuntut adanya perubahan politik dan administratif yang signifikan untuk memfasilitasi upaya pengurasan kopi dari setiap kampung.75 Pada
74 Audrey Kahin, Dari Pemberontakan ke Integrasi, cet-2, 257. 75 Kebijakan ini berimbas pada kedudukan penghulu di tiap nagari. Penghulu di
tiap nagari yang pada awalnya mengurasi kampung secara bersamaan, berdasarkan
FORMALISASI NILAI ADAT MINANGKABAU ... | 143
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
tahun 1915, Belanda memberlakukan Nagari Ordantie sebagai sebuah cara untuk mempromosikan otonomi kampung yang lebih besar dalam kerangka politik etis.
Dewan Nagari (Nagari-Raad) yang hanya terdiri dari penghulu inti (penghulu yang berasal dari puak keturunan pendiri nagari) dibentuk untuk melaksanakan kehendak pemerintah kolonial Belanda.76 Dewan Nagari ditetapkan sebagai tingkat terendah dalam sistem adminstrasi kolonial. Dewan ini berdampingan dengan dewan adat yang dikenal dengan istilah rapat penghulu yang melemahkan posisi penghulu. Dalam masyarakat Minangkabau, ketegangan antara penghulu konservatif yang menekankan identitas Minangkabau dan ingin melestarikan adat Minangkabau dengan kaum modernis Islam atau yang juga dikenal dengan kelompok nasionalis sekuler yang lebih menyukai sebuah identitas nasional yang mengindonesia semakin berkembang.77 Regionalisme Minangkabau, nasionalisme radikal, komunisme dan modernisme Islam saling bertarung antara yang satu dengan yang lainnya.
Campur tangan pemerintah dalam urusan nagari terus berlanjut hingga masa kemerdekaan. Perubahan terhadap susunan kelambagaan nagari terjadi seiring dengan ditetapkannya Maklumat Residen Sumatera Barat Nomor 20 dan 21 pada tanggal 21 Mei 1946. Perubahan ini terjadi setelah mendengar hasil Rapat Pleno Komite Nasional Keresidenan Sumatera Barat pada tanggal 18 Maret 1946 yang menyatakan bahwa dengan pertimbangan menegakkan demokrasi serta memperlancar pemerintahan dan pembangunan nagari-nagari. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur-unsur pemerintahan nagari adalah Wali Nagari, Dewan Perwakilan Nagari dan Dewan Harian Nagari. Berdasarkan ketetapan ini, maka Wali Nagari mempunyai kedudukan yang kuat karena sekaligus menjabat sebagai ketua DPN dan DHN78 yang berlaku umum di Sumatera Barat.
Pada masa pemerintahan orde lama, Pemerintahan Nagari berkedudukan di bawah camat. Pada dekade ini terlihat besarnya campur tangan pemerintahan pusat dalam mengatur kehidupan masyarakat dalam
kebijakan ini mereka kemudian harus memilih salah satu di antara mereka untuk menjadi penghulu kepala (nagarihoofd). Renske Biezeveld, “Ragam Peran Adat”, 232.
76 A. Oki, “Economic Constrains, Social Change dan The Communist Uprising in West Sumatera (1926-1927): A Critical Review of B.J.O. Schrike’s West Coast Report”, dalam Change and Continuity in Minangkabau: Local, Regional and Historical
Perspectives on West Sumatera, eds. L.L. Thomas & Franz von Benda-Beckmann (Ohio: CSAS, 1985), 225.
77 Renske Biezeveld, “Ragam Peran Adat”, 233. 78 Efi Yandri, Nagari dalam Prespektif Sejarah (Padang: Lentera 21, 2003), 61.
144 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
nagari. Kemerdekaan yang secara utuh yang menjadi dambaan setiap anggota masyarakat ternyata belum terwujud. Bahkan pemerintahan pada masa ini masih mempertahankan kebijakan pemerintah kolonial yang menghancurkan sendi-sendi institusional masyarakat adat tradisional. Bahkan, bisa disimpulkan bahwa kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pada masa ini berupa estafet dari kebijakan yang sudah ada sebelumnya pada masa kolonial.79 Beberapa regulasi yang dibentuk pada masa orde lama yang menunjukkan besarnya campur tangan pemerintah pusat terhadap kehidupan nagari, sebagai berikut:
1. Maklumat residen Sumatera Barat Nomor 20-21 Tahun 1946. Berdasarkan maklumat ini, maka struktur kelembagaan nagari terdiri dari Wali Nagari, Dewan Perwakilan Rakyat Nagari (DPRN) dan Dewan Harian Nagari (DHN). Wali Nagari merupakan penguasa tunggal pada tingkat nagari yang merangkap sebagai Ketua DPRN dan DHN. Struktur yang dibentuk dalam maklumat ini tidaklah demokratis, karena semua aspek kekuasaan dipegang secara tunggal oleh Wali Nagari;
2. Peraturan daerah Sumatera Tengah Nomor 50/GP/1950 tentang Pengaturan Nagari berdasarkan UUDS 1950. Regulasi ini menetapka penghapusan bentuk pemerintahan nagari yang kemudian digantikan oleh pemerintahan wilayah. Kondisi ini menimbulkan keresahan dan tantangan bagi masyarakat dan para pemangku adat. Konfrensi ninik mamak dan pemangku adat yang dilaksanakan di Bukittinggi pada tahun 1953 memutuskan untuk menghidupkan kembali sistem pemerintahan nagari. Hasil konfrensi ini kemudian dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Februari 1954 yang menyatakan untuk menghidupkan kembali sistem pemerintahan nagari;
3. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2/GSB/KN/1958 yang menetapkan bahwa Pemerintahan Nagari dilakukan oleh Kerapatan Nagari;
4. Surat Penyuara perang Sumbar tahun 1959 yang menyatakan penyatuan Pemerintahan Nagari, dan;
5. Surat Keputusan Gubernur Nomor 02/Desa/GSB/1962 tentang Pengaturan Nagari dalam Daerah Sumatera Barat. Surat keputusan ini didasari oleh adanya azaz demokrasi terpimpin yang dianut pada masa itu. Susunan pemerintahan nagari terdiri dari kepala nagari, badan musyawarah nagari dan musyawarah gabungan. Di
79 Nofil Ardi, “Pemerintahan Nagari”, 152.
FORMALISASI NILAI ADAT MINANGKABAU ... | 145
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
samping itu, juga ada pamong nagari, panitera nagari dan pegawai nagari. Surat keputusan ini memberikan peranan yang besar bagi kepala nagari karena kepala nagari mempunyai kedudukan sebagai ketua musyawarah gabungan nagari.
Pada awal 1970-an, desa-desa masih melaksanakan dua bentuk
pemerintahan. Namun kondisi ini mengalami perubahan drastis ketika rezim Orde Baru memaksakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Regulasi ini mulai diterapkan di Sumatera Barat pada tahun 1983.80 Pemberlakuan undang-undang ini berimplikasi pada penghapusan nagari sebagai satuan unit pemerintahan terkecil dalam pemerintahan lokal. Setiap perkampungan atau yang dikenal dengan istilah jorong, yang membentuk nagari, diakui sebagai sebuah desa terpisah semenjak diberlakukannya regulasi tersebut. Dengan demikian, nagari yang sudah ada sebelumnya dipecah menjadi beberapa desa.
Terdapat beberapa penekanan dalam regulasi pemerintahan desa. Pertama, penekanan pandangan bahwa pemerintahan desa membutuhkan penguatan untuk secara efektif meningkatkan partisipasi dalam program pembangunan. Penekanan kedua adalah adanya kebutuhan akan adanya penyeragaman bentuk pemerintahan desa (berdasarkan model Jawa). Regulasi ini mendefenisikan bahwa desa sebagai tingkatan paling rendah dalam pemerintahan daerah, namun hanya memiliki sedikit saja dari tugas-tugas otonominya. Secara administrasi, keberhasilan penerapan sistem pemerintahan desa merupakan prestasi besar pada skala nasional. Namun, pada tatanan masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat terjadi implikasi dengan munculnya dikotomi81 antara pelaksanaan pemerintahan yang dijalankan oleh administrator pemerintah dengan tokoh adat yang menjadi panutan dan harmonisasi tatanan sosial kemasyarakatan yang sudah tumbuh sejak lama.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 sangat melemahkan posisi adat.82 Hal ini dikarenakan adanya padangan dalam adat yang menyatakan bahwa nagari merupakan sebuah kesatuan politik yang mempunyai peran penting. Dalam perkembangannya, ternyata regulasi ini sulit untuk diterapkan dan justru berimplikasi sebaliknya. Kedudukan
80 Franz and Keebet von Benda-Beckmann, “Recentralization and
Decentralization”, 293. 81 Nofil Ardi, “Pemerintahan Nagari”, 148. 82 Bahkan regulasi ini terlihat membuat pembatasan secara tajam antara unsur
adat dengan unsur pemerintahan desa. Nofil Ardi, “Pemerintahan Nagari”, 154.
146 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
regulasi ini justru semakin mendorong keinginan masyarakat untuk mempertahankan hukum adat. Status politik sampai pada tingkatan tertentu kemudian dipulihkan dalam nagari ketika para pemimpin adat diperkenankan untuk membentuk Kerapatan Adat Nagari (KAN) guna menyelesaikan beberapa persoalan83 yang melebihi batas dan cakupan pemerintah desa. Kondisi ini menggambarkan bahwa pemerintah bersifat ambivalen dalam menetapkan suatu kebijakan. Pada satu sisi, pemerintah tetap mengakui dan menghargai adanya pranata adat. Di sisi lain, memerintah melakukan pemasungan demokrasi dengan unifikasi kebijakan.
Realita lain yang menarik untuk disimak terkait upaya unifikasi ini adalah dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Nomor 08 Tahun 1994 tentang Pedoman Acara Penyelesaian Sengketa Adat Nagari. Aturan secara tidak langsung telah menghapuskan keragaman tata cara penyelesaian sengketa sebagaimana yang sebelumnya sudah diatur dalam adat salingka nagari (adat sekitar nagari). Berdasarkan keputusan ini, penyelesaian sengketa berakhir dengan adanya pemutusan oleh KAN. Kondisi secara jelas menggeser fungsi dan kedudukan KAN menjadi sebuah lembaga yudikatif. Sementara pada awalnya KAN dibentuk sebagai sebuah lembaga mediasi dalam perkara-perkara yang terjadi dalam atau antarnagari.
Kebijakan pemerintah pusat untuk mengadakan unifikasi bentuk pemerintahan daerah terendah dalam bentuk pemerintahan desa menimbulkan beberapa efek negatif terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan di Minangkabau. Implikasi regulasi tersebut telah menghancurkan pranata dan struktur masyarakat adat, sebagai berikut.84
1. Melemahnya management competence. Kondisi telah menggiring adanya pergeseran pandangan atau desakralisasi kedudukan pemangku adat oleh anak kemenakan, terkhusus bagi generasi
83 Beberapa persoalan yang dimaksudkan seperti pengelolaan tanah komunal
dan distribusi air dalam hal irigasi sawah. Lembaga ini juga mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sendiri beberapa sengketa setempat sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri. Franz & Keebet von Benda-Beckmann, “Actualishing History for Binding the Future: Decentralization in Minangkabau”, dalam Resonances and
Dissonances in Development: Actors, Networks and Cultural Repertoires, eds. P. Hebinck & G. Verschoor (Assen: Van Gorcum, 2001), 10-11. KAN dibentuk berdasarkan Perda Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983. Nofil Ardi, “Pemerintahan Nagari”, 148. Kondisi seperti inilah yang kemudian mengalami perluasan dan revitalisasi pada saat sekarang ini dan lebih dikenal dengan istilah restorative justice. Restorative
justice merupakan salah satu upaya yang ditempuh dalam menyelesaikan beberapa perkara tindak pidana ringan di luar jalur hukum positif.
84 Nofil Ardi, “Pemerintahan Nagari”, 149-150.
FORMALISASI NILAI ADAT MINANGKABAU ... | 147
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
muda yang mengenyam pendidikan formal dan terbawa arus modernisasi;
2. Missing generation. Arus modernisasi berdampak pada menurunnya minat generasi muda untuk mempelajari adat, sehingga proses regenerasi tidak berjalan dengan baik. Minimnya pengetahuan adat dalam pendidikan formal juga tidak ditunjang oleh pendidikan non-formal. Pada masa sebelumnya, di Minangkabau masyarakat mempunyai budaya surau sebagai sebuah informal education dalam upaya pembentukan pribadi anak nagari secara lahir dan batin;
3. Weakness of institution. Fenomena sosiologis yang berkembang di kalangan masnyarakat adalah adanya pergeseran nilai-nilai mamak, yang pada awalnya merupakan benevolent institution menjadi predatory institution. Kondisi ini berimbas pada hilangnya kepercayaan pada fungsi dan kedudukan mamak.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang
Pemerintahan Desa, nagari kehilangan statusnya sebagai sebuah organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat. Sistem pemerintahan nagari digantikan oleh sistem pemerintahan desa dalam upaya unifikasi bentuk sistem pemerintahan nasional. Sebelum memasuki era otonomi daerah, pada dasarnya wacana pemerintahan nagari di Sumatera Barat sudah ada dan terbukti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983. Pasal 1 huruf (e) Peraturan Daerah ini menyebutkan bahwa nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.
Berdasarkan regulasi ini, meskipun nagari diakui sebagai sebuah kesatuan hukum adat yang mempunyai wilayah dan kekayaan tertentu, namun nagari tidak mempunyai hak dan wewenang dalam pemerintahan. Nagari hanya mengatur tata hubungan kehidupan masyarakat nagari sepanjang adat. Pelaksanaan tugas ini berada dalam kewenangan lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN). Nagari secara tidak langsung telah ditransformasikan menjadi sebuah unit kesatuan adat dan ekonomi. Bahkan dalam setiap upaya menetapkan sebuah kebijakan, seorang Kepala Desa diharuskan merujuk kepada Keputusan KAN. Meskipun demikian, dalam kenyataannya pemerintahan desa mempunyai kedudukan yang lebih kuat karena merupakan pemerintahan terendah yang menjadi ujung tombak pemerintahan pusat. Kondisi ini semakin meredupkan
148 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
demokrasi yang sudah lama hidup dan berkembang dalam pemerintahan nagari.85
Pada tahun 2000, Sumatera Barat menerapkan semangat pergerakan kembali ke nagari. Semangat pergerakan ini mengundang banyak perhatian dari luar Sumatera Barat sendiri. Kembali ke nagari yang dipahami di Minangkabau sebagai sebuah upaya untuk kembali pada tradisi politik adat tradisional yang lebih tua dan sebagai sebuah upaya revitalisasi kedudukan adat pada umumnya.86 Pada Januari 2001, regulasi yang berkenaan dengan otonomi daerah telah diterapkan. Salah satu unsur terpenting di dalamnya adalah pembaharuan demokratis pemerintahan desa yang substansial. Hal ini termasuk juga dalam pengenalan BPD (Badan Perwakilan Desa) dan pemisahan kekuasaan antara badan ini dengan lembaga eksekutif tingkat desa, yaitu kepala desa beserta jajaran stafnya. Labih jauh lagi, berdasarkan undang-undang ini dapat dilihat bahwa pemerintahan desa pada saat ini dapat berlandaskan asal-usul dan adat istiadat. Di Sumatera Barat, hak untuk melandaskan pemerintahan desa pada hak-hak asal usul dan adat istiadat setempat dengan segera memberikan implikasi pada penghapusan desa dan penyatuan nagari kembali. Intervensi yang dilakukan pihak pemerintah terhadap KAN pada era pemerintahan desa menyisakan sedikit kewenangan kepada nagari untuk mengatur dirinya sendiri. KAN hanya berwenang sebagai pelaksana dan pengawas terhadap pelaksanaan adat dalam lingkungan nagari saja tanpa mempunyai kekuatan dalam pelaksanaan pemerintahan.
Penetapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan legalitas formal terhadap adanya perubahan paradigma sebagai wujud nyata reformasi pemerintahan berskala nasional. Hal pokok dalam penyelenggaraan pemerintah berdasarkan regulasi ini adalah adanya pengurangan sistem pengaturan penyelenggaraan pemerintah secara terpusat (sentralistik), dengan kebijakan yang didominasi oleh pemerintah pusat (top down) ataupun secara bottom up untuk mengkoodinir aspirasi masyarakat. Regulasi ini mengisyaratkan pelaksanaan otonomi daerah yang bercirikan asas desentralisasi, memposisikan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab utama atas kebijakan penyelenggaraaan pemerintah sesuai dengan kewenangan yang diberikan, dan harus tetap berada dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.
85 Mochtar Naim, Perspektif Nagari Ke Depan (Padang: Lentera 21, 2003), ix. 86 Franz & Keebet von Benda-Beckmann, “Recentralization and
Decentralization”, 293.
FORMALISASI NILAI ADAT MINANGKABAU ... | 149
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Penyerahan kewenangan yang luas kepada daerah dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan berlangsung lebih efektif dan efisien sesuai dengan kondisi riil yang dibutuhkan oleh masyarakat daerah setempat. Kondisi ini bertujuan agar pelayanan kepada masyarakat terselenggara secara lebih baik dan memenuhi harapan masyarakat. Perubahan paradigma pemerintahan dari asas sentralistik menjadi desentralisasi menuntut kemampuan Pemerintah Daerah untuk dapat merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan potensi daerah serta pemanfaatan secara optimal.
Ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah disambut positif oleh Pemerintah Sumatera Barat dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari. Kondisi ini memberikan peluang kepada setiap nagari untuk bisa mengembangkan potensi masing-masing wilayahnya. Hal ini didukung dengan adanya penyerahan lebih dari 105 wewenang kepada Pemerintah Nagari. Berdasarkan regulasi ini, nagari dinyatakan sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang terdiri dari beberapa suku, mempunyai wilayah dan batas-batas tertentu, mempunyai kekayaan sendiri dan berwenang mengurus dirinya sendiri serta memilih pimpinan pemerintahannya. Seiring dengan adanya amandemen terhadap regulasi otonomi daerah dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Sumatera Barat juga melakukan evaluasi dan amandemen terhadap Perda Nagari. Amandemen dilakukan terhadap Perda Nomor 9 Tahun 2000 menjadi Perda Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari. Penetapan perda Nomor 2 Tahun 2007 ini mencabut menyatakan tidak belakunya Perda Nomor 9 Tahun 2000.87 Ada beberapa alasan adanya penyesuaian dan penyempurnaan perda nagari,88 sebagai berikut :
1. Mengurangi beberapa kemungkinan munculnya masalah-masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari;
2. Menampung berbagai pendapat yang mendorong terciptanya demokrasi yang mencerminkan musyawarah dan mufakat di nagari, dan;
87 Keterangan lebih lanjut bisa dilihat dalam BAB XIV Ketentuan Penutup
pasal 38 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari.
88 Penjelasan umum Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari.
150 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
3. Meningkatkan kinerja Pemerintahan Nagari dengan prinsip-prinsip good governance, clean governance dan pemerintahan yang mandiri. Meskipun demikian, kedua perda ini mempunyai hubungan erat
yang membuktikan bahwa telah terjadi positivisasi nilai-nilai adat dalam sistem hukum nasional. Dalam upaya positivisasi tersebut memang tidak menutup kemungkinan adanya beberapa perubahan terhadap sistem pemerintahan nagari di Minangkabau klasik. Beberapa perubahan tersebut pada dasarnya hanyalah dari segi formalitas dengan tidak mempengaruhi nilai-nilai dasar dan substansi yang ada dalam sistem pemerintahan nagari yang sudah ada sebelumnya.
Merujuk pada kedua peraturan daerah ini, ada beberapa substansi pokok dalam pemerintahan nagari yang mempunyai kedudukan penting dalam upaya mempertahankan bentuk asli sistem pemerintahan masyarakat Minangkabau. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai susunan asli khususnya dalam wilayah daratan Sumatera Barat yang sudah dikenal sejak lama. Pada saat diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa secara nasional, Pemerintah Daerah Sumatera Barat menindaklanjutinya dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 162/GSB/1983. Keberadaan nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam Provinsi Sumatera Barat dipertahankan keutuhannya berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.
Penyesuaian penggunaan istilah dari desa menjadi nagari89 berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tidak hanya dilaksanakan pada aspek-aspek formalitas semata. Implikasi penggantian istilah ini mempunyai konsekuensi logis terhadap konstruksi sistem pemerintahan pada tingkat terendah. Ada beberapa dasar pemikiran yang mendorong penyesuaian istilah tersebut. Pertama, wilayah daratan Sumatera Barat pada dasarnya merupakan satuan kebudayaan yang homogen sehingga hampir tidak ditemukan heterogenitas yang terbagi atas beberapa sub kultur/etnis menurut wilayah administrasi pemerintahan. Kedua, adanya keinginan dan aspirasi dari
89 Secara yuridis, peluang untuk penyesuaian nama ini dinyatakan dalam pasal 1 huruf (o) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, “... desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang dikaui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten”.
FORMALISASI NILAI ADAT MINANGKABAU ... | 151
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
masyarakat untuk kembali pada sistem pemerintahan nagari.90 Hal ini merupakan hasil pertemuan dan kesepakatan dalam musyawarah yang dilaksanakan dengan unsur kemasyarakatan Sumatera Barat baik yang berada di daerah rantau ataupun yang berada dalam Pemerintahan Kabupaten. Penyesuaian istilah ini juga disertai dengan perubahan filosofi pemerintahan dari susunan dan bentuk pemerintahan yang sentralistis dan birokratis menjadi sistem pemerintahan yang demokratis, memiliki kemandirian, peran seluruh unsur kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari otonomi asli sebagaimana yang dianut dalam regulasi otonomi daerah.
Adanya kewenangan yang diserahkan kepada Pemerintahan Provinsi dalam beberapa aspek dalam upaya efiseinsi pemerintahan dan efektivitas pemerintahan dimanfaatkan oleh Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat untuk melestarikan nilai-nilai adat. Hal ini terbukti dengan adanya pengakuan eksistensi dan pelestarian nilai-nilai asli daerah dalam bentuk adat istiadat pada tingkatan daerah dan dinyatakan dalam Perda Sumbar Nomor 2 Tahun 2007, sebagai berikut.
Bab XIII Ketentuan Tambahan (1) Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat mengakui dan
menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat; (2) Pembinaan dan pelestarian adat istiadat dilakukan oleh
masyarakat adat, pemangku adat, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi.
Adanya pengakuan eksistensi adat istiadat dalam wilayah
Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat membuktikan bahwa institusi otonomi daerah dan desentralisasi kekuasaan memberikan fasilitas dalam upaya penguatan dan pelestarian nilail-nilai kearifan lokal. Dalam konteks masyarakat hukum adat Minangkabau di Sumatera Barat, nilai-nilai kearifan lokal terjabarkan dalam adagium adat basandi syarak, syarak
basandi Kitabullah. Adagium ini menunjukkan kekhasan masyarakat hukum adat Minangkabau yang mempunyai keterkaitan antara adat dan Islam. Hubungan adat dan Islam dalam masyarakat adat Minangkabau tidak bisa dipisahkan. Di antara keduanya tidak bisa dianggap sebagai dua
90 Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Nota Penjelasan Gubernur
Sumatera Barat mengenai Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 14 September 2000.
152 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
eksponen yang berlainan dan berlawanan.91 Meskipun demikian, dalam rangka penerapan dan pelestariannya dibutuhkan beberapa akomodasi agar sistem pemerintahan nagari bisa terlaksana secara proporsional dan profesional.
B. Eksistensi Nagari
Pemerintahan daerah dan pemerintahan nagari merupakan bentuk sistem pemerintahan otonomi. Hal ini dikarenakan nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. Nagari terbentuk dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah tertentu, harta kekayaan sendiri, mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri serta memilih pimpinan daerahnya sendiri.92 Lebih rinci lagi dinyatakan bahwa nagari dalam hal kepengurusan dan pengaturan kepentingan masyarakat dalam nagari harus didasarkan kepada filosofi adat Minangkabau (adat basandi syarak,
syarak basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.93 Terkait hal ini, disinggung juga konsep daerah otonom. Daerah otonom merupakan suatu kesatuan hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu, berwenang dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Nagari merupakan bentuk daerah otonom yang mempunyai wewenang dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Nagari merupakan bentuk pemerintahan otonom dan terdepan di
91 Lebih lengkap lagi, Hamka menyimpulkan bahwa sangat sulit untuk
memisahkan antara adat dan agama Islam dalam masyarakat Minangkabau. Perpaduan di antara keduanya bukanlah seperti percampuran minyak dengan air dalam larutan susu. Islam bukanlah tempelan-tempelan dalam adat Minangkabau. Hamka, Ajahku: Riwayat
Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah dan Perdjuangan Kaum Agama di Sumatera (Jakarta: Djajamurni, 1967), cet-3, 22.
92 Defenisi ini dirujuk dari pasal 1 angka (7) Perda Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari. Setelah ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah Sumatera Barat melakukan evaluasi dan penyelarasan dan singkronisasi sehingga ditetapkannya Perda Nomor 2 Tahun 2007. Dalam pasal 2 dinyatakan bahwa nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai batasan-batasan wilayah tertentu dan berwenang dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam hal adat istiadat.
93 Keterangan lebih lanjut bisa disimak dalam pasal 1 angka (7) Perda Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari.
FORMALISASI NILAI ADAT MINANGKABAU ... | 153
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Sumatera Barat. Nagari mempunyai identitas budaya tradisional berupa hukum adat, sistem penguasaan ulayat, sistem kekerabatan dan bahkan sistem politik pada tingkat nagari yang berinteraksi dengan sistem politik pemerintahan formal.94 Pemerintahan Nagari mempunyai tanggung jawab terhadap pemerintahan dan pembangunan dengan mengacu pada kepentingan nagari, daerah dan nasional yang sesuai dengan konstitusi. Nagari sebagai institusi lokal juga merupakan instrumen dalam membangun demokrasi yang sesungguhnya.
Pengakuan kedudukan nagari secara konstitusional pada awalnya ditemukan dalam Undang-undang Dasar 1945 sebelum dilakukan amandemen. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa pembagina daerah di Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk dan susunan yang ditentukan berdasarkan undang-undang dengan menimbang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemeritnahan negara dan hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Lebih jauh lagi, penjelasan pasal 1895 menyatakan bahwa dalam teritori Negara Republik Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelfbestuurende
landschappen dan volksgemenschaapens seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut memiliki susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah istimewa. Pemerintah Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara mengenai daerah-daerah tersebut akan mengingati asal usul daerah tersebut.
Keberadaan penjelasan pasal ini mengalami amandemen pada tahun 2000 dan terdapat penambahan pasal dan perubahan redaksi pasal terkait dengan pengakuan terhadap adanya bentuk pemerintahan pada tingkat lokal. berdasarkan pasal 18B ayat (2)96, mulai dipergunakan frasa
94 Nurul Firmansyah, “Peluang dan Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Alam
Berbasis Nagari” (Makalah yang dipresentasikan dalam Musyawarah Adat: Aplikasi Majemen Suku dan Pemberdayaan Hukum Adat dalam Hukum Nasional di Solok 24 Maret 2012), 11.
95 Penjelasan ini juga dipakai dalam penjelasan umum Perda Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pemerintahana Nagari.
96 Setelah amandemen ke-4 Undang-undang Dasar 1945 dilakukan, pemerintah menyesuaikan regulasi otonomi daerah dengan menetapkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Terkait dengan pemerintahan desa, dalam pasal 18B ayat (1) dinyatakan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
154 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
kesatuan masyarakat hukum adat. Menurut Hazairin, sebagaimana yang dikutip Alidinar Nurdin,97 masyarakat hukum adat merupakan kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan untuk berdiri sendiri karena mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Apabila diperhatikan lebih lanjut, ada perbedaan mendasar dalam konsep masyarakat hukum adat dengan kesatuan masyarakat hukum adat. Jimly Asshidiqie menjelaskan bahwa masyarakat merupakan kumpulan individu yang hidup dalam lingkungan pergaulan bersama sebagai sesuatu community atau society. Sementara itu, term kesatuan masyarakat menunjuk kepada pengertian masyarakat organik yang tersusun dalam kerangka kehidupan berorganisasi dengan saling mengikatkan diri untuk kepentingan mencapai tujuan bersama. Secara sederhana, masyarakat hukum adat sebagai unit organisasi masyarakat hukum adat itu harus dibedakan dari masyarakat hukum adatnya sendiri sebagai isi dari kesatuan organisasinya itu.98
Nagari merupakan mikrokosmos politis tata pemerintahan adat99 Minangkabau yang lebih luas, selaras dengan fundamen-fundamen dasar dasar adat, matri klan dan bahasa.100 Sebuah nagari tidak hanya dipandang sebagai sebuah wilayah administrasi pemerintahan saja. Akan tetapi, nagari juga dimaknai sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum adat Minangkabau. Implikasinya adalah bahwa seluruh warga masyarakat secara bersama mempunyai kewajiban untuk mengembangkan potensi nagari dalam bentuk sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Setiap anggota masyarakat juga mempunyai keharusan untuk mengembangkan nilai-nilai keislaman, adat dan budaya dalam nagari. Hal ini sesuai dengan falsafah adat salingka nagari dan adat
sabatang panjang guna ketercapaian dan kesuksesan penyelenggaraan
97 Alidinar Nurdin, “Pentingnya Tanah Ulayat dalam Otonomi Nagari di
Provinsi Sumatera Barat” (Makalah yang dipresentasikan dalam Musyawarah Adat: Aplikasi Manajemen Suku dan Pemberdayaan Hukum Adat dalam Hukum Nasional, Solok 23 Maret 2012), 5.
98 Jimly Asshidiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-undang (Jakarta: Sekjend dan Kepaniteraan MK, 2005), 77.
99 Semenjak masa kolonialisasi Belanda, nagari sudah menjadi sebuah unit sosio-politis yang otonom. Kondisi sosio-politis dan struktur hukumnya sebagian besar ditetapkan melalui adat, meskipun dalam perkebangan selanjutnya juga dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Keebet von Benda-Beckmann, “The Social Significance of Minangkabau State Court Decisions”, Journal of Legal Pluralism, 23 (1985): 12.
100 Franz and Keebet von Benda-Beckmann, “Identitas-identitas Ambivalen”, 549.
FORMALISASI NILAI ADAT MINANGKABAU ... | 155
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat dan anak nagari.
Nagari mempunyai batasan-batasan wilayah tertentu dan berwenang dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam hal adat istiadat. Wilayah nagari meliputi wilayah hukum adat dengan batasan-batasan tertentu yang sudah berlaku secara turun temurun dan diakui sepanjang adat. Ketentuan yang berkaitan dengan wilayah sebuah nagari sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 dan 3 Perda Nomor 2 Tahun 2007, pada dasarnya merupakan bentuk formalisasi bediri dan diakuinya sebuah nagari. Apabila diperhatikan, untuk berdirinya sebuah nagari di Minangkabau ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.
Masyarakat Minangkabau mempunyai undang-undang berdirinya sebuah nagari.101 Berdirinya sebuah nagari yang utuh dan diakui dalam konteks masyarakat Minangkabau harus memenuhi tiga aspek utama. Masing-masing aspek tersebut juga mempunyai beberapa persyaratan yang bertujuan untuk menjamin terlaksananya aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat.
1. Aspek Wilayah dan Kepemimpinan102
Sebuah nagari di Minangkabau terdiri dari kumpulan beberapa wilayah yang lebih kecil. Wilayah-wilayah inilah yang berperan penting dalam membentuk sebuah nagari. a. Taratak merupakan wilayah yang dijadikan sebagai tempat tinggal
sementara hingga ditemukannya tempat tinggal baru yang lebih baik untuk dijadikan tempat tinggal tetap. Setelah menemukan tempat tinggal permanen yang baru, sesekali masyarakat kembali ke taratak dengan tujuan bercocok tanam ataupun untuk membuat kolam. Keberadaan taratak mengindikasikan adanya harta masyarakat yang dibuktikan dengan adanya upaya pengelolaan
101 Dalam pepatah Minangkabau dinyatakan bahwa nagari bapaga undang-
undang, kampuang bapaga jo pusako (sebuah nagari dipagari dengan undang-undang, sebuah kampung dipagari dengan harta pusaka). Edison M.S. dan Nasrun, Tambo
Minangkabau: Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2010), 156.
102 Pepatah Minangkabau menyatakan bahwa taratak mulo dibuek, sudah taratak manjadi dusun, sudah dusun manjadi koto, sudah koto manjadi nagari (pada awalnya terbentuk dengan adanya taratak, setelah beberapa taratak terbentuk akan menjadi dusun, setelah beberapa dusun terbentuk akan menjadi koto, setelah beberapa koto terbentuk maka akan menjadi nagari). Ibrahim Dt. Sanggoeno Dirajo, Tambo Alam
Minangkabau: Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang (Bukittinggi: Kristal Multi Media, 2009), 84.
156 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
terhadap wilayah yang pernah mereka tinggali untuk sementara waktu.
b. Kampuang merupakan tempat tinggal yang ditempati oleh beberapa keluarga saparuik (sub-lineage). Keluarga saparuik merupakan beberapa keluarga besar yang berasal dari satu ibu kandung.
c. Dusun merupakan tempat tinggal yang ditempati oleh beberapa keluarga saparuik dari suku103 yang berbeda. Biasanya ada batasan jelas104 antara tempat tinggal salah satu keluarga saparuik dengan keluarga saparuik lainnya.
d. Koto merupakan kumpulan dari beberapa dusun yang dipimpin oleh seorang datuk atau penghulu. Datuk atau penghulu ini dianggap sebagai Tuo Koto. Tuo Koto merupakan tokoh yang dituakan dan dijadikan panutan dalam wilayah koto. Tuo Koto berhak mempunyai staff yang terdiri dari para penghulu dan bertugas membantunya dalam urusan-urusan intern koto. Dalam sebuah koto terdapat dua atau tiga suku yang berbeda.
e. Nagari merupakan kumpulan beberapa koto. Sebuah nagari harus mempunyai minimal 4 suku. Secara hierarkis kepemimpinannya, himpunan Mamak Kapalo Kaum pada tingkatan suku dipimpin oleh seorang Datuak Tuo Kampuang. Himpunan Datuak Tuo
Kampuang dipimpin oleh seorang Datuak Ampek Suku atau yang dikenal juga dengan Datuak Lantak Suku.
2. Aspek Sarana Prasarana105
Guna menjamin terlaksananya aktivitas masyarakat dengan baik dalam kehidupan bernagari, ada beberapa sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh setiap nagari, sebagai berikut.
103 Suku merupakan himpunan beberapa keluarga saparuik yang dipimpin oleh
seorang Penghulu Andiko dan bisa disebut dengan Mamak Kapalo Kaum. 104 Batas-batas tersebut biasanya ditandai bintalak atau lantak, sebentuk tiang
pancang yang ditancapkan di tanah. Pembatasan ini berhubungan dengan kepemilikan harta pusaka kaum.
105 Pepatah Minangkabau menyatakan bahwa cupak salingka batuang, adat
salingka nagari, balabuah nan golong, ba pasa nan rami, babalai bamusajik,
bagalanggang, batapian tampek mandi (cupak selingkar bambu, adat selingkaran nagari, mempunyai jalan yang datar, mempunyai pasar yang ramai, mempunyai balai adat dan mesjid, mempunyai gelanggang, mempunyai sumber air untuk dijadikan tempat mandi). Julius Dt. Malako Nan Putiah, Mambangkik Batang Tarandam, 161. Dalam literatur lain, aspek sarana dan prasarana nagari ini dikenal juga dengan term sumarak nagari. Sebagai bahan perbandingan bisa disimak dalam Ibrahim Dt. Sanggoeno Dirajo, Tambo
Alam Minangkabau, 91.
FORMALISASI NILAI ADAT MINANGKABAU ... | 157
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
a. Basosok bajarami, maksudnya adalah setiap nagari diharuskan mempunyai batas-batas kenagarian yang jelas. Penetapan batas-batas nagari ditentukan berdasarkan rapat musyawarah antar beberapa nagari yang berdekatan. Rapat ini dilaksanakan oleh para penghulu antar nagari. Sebuah nagari diharuskan mempunyai daerah asli atau daerah asal. Hal ini berkaitan erat dengan eksistensi beberapa adat istiadat yang berbeda dari masing-masing nagari.106 Pembatasan ini juga berkaitan dengan keberadaan tanah ulayat antara satu nagari dengan nagari lainnya.
b. Balabuah batapian. Balabuah (labuah = jalan) maksudnya adalah setiap nagari diharuskan mempunyai sarana jalan lingkungan dalam nagari dan juga sarana jalan antar nagari yang berguna untuk menghubungkan antar sesama nagari. Batapian (tapian=sungai/tempat mandi) maksudnya setiap nagari diharuskan mempunyai tempat mandi. Keharusan mempunyai tempat mandi ini dimaksudkan untuk menjamin kelancaran dan terlaksananya kegiatan MCK setiap anggota masyarakat.
c. Barumah tanggo maksudnya adalah setiap nagari harus mempunyai rumah yang dijadikan sebagai tempat tinggal. Hal ini merupakan syarat mutlak dalam sebuah nagari. Keharusan setiap nagari mempunyai rumah tangga dalam konteks ini ditujukan pada kepemilikan rumah gadang (rumah adat masyarakat Minangkabau), baik itu dalam lingkungan rumah gadang sakaum ataupun rumah gadang keluarga saparuik. Keberadaan rumah gadang ini juga bisa dijadikan sebagai patokan dalam menelusuri nasab dan hubungan kekeluargaan seseorang yang masyarakat Minangkabau.
d. Bakorong bakampuang maksudnya adalah setiap nagai harus terdiri dari beberapa wilayah yang lebih kecil. Seperti halnya dalam aspek kewilayahan dan kepemimpinannya, keharusan adanya korong (jorong) dan kampuang dimaksudkan untuk menunjukkan keharusan adanya pemersatu rasa di antara sesama penduduknya, serasa, seadat, selembaga dan lain sebagainya.
106 Pepatah Minangkabau menyatakan bahwa adat salingka nagari (adat
selingkar nagari). Maksud pepatah ini adalah setiap nagari mempunyai adat istiadat yang otonom dan diakui dalam Alam Minangkabau. Adat istiadat sebuah nagari tidak bisa diintervensi oleh nagari lainnya, sehingga membutuhkan pembatasan wilayah yang jelas. Terkait hal ini, lebih lanjut dijelaskan bahwa institusi dan pluralitas hukum pada tingkat nagari merupakan salah satu bagian dari kompleksitas karakteristik pluralime hukum di Indonesia. Keebet von Benda-Beckmann, “The Social Significance of Minangkabau”, 14.
158 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Keseluruhan itu menggambarkan sebuah kesatuan yang utuh dalam lingkungan masyarakat.
e. Basawah baladang maksudnya adalah setiap nagari di Minangkabau harus mempunyai lahan pertanian dalam bentuk sawah atau ladang. Hal ini menunjukkan keharusan akan adanya sumber ekonomi yang menjadi penopang kehidupan masyarakat dalam nagari.
f. Babalai bamusajik maksudnya adalah setiap nagari di Minangkabau harus mempunyai balai sebagai pusat perkumpulan serta mesjid sebagai sarana penunjang ibadah. Syarat ini menunjukkan bahwa antara adat Minangkabau dengan ajaran Islam merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau, dikenal ada 3 bentuk balai, sebagai berikut: 1) Balai adat (balairung) merupakan tempat musyawarah bagi
ninik mamak atau penghulu dalam nagari dalam menyelesaikan persoalan-persoalan adat, sako pusako dan lain sebagainya;
2) Balai gelanggang merupakan tempat yang dipergunakan untuk berbagai kegiatan dan pusat keramaian seperti pesta rakyat dan lain sebagainya, dan;
3) Balai pakan (pasar) merupakan tempat yang menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat.
g. Bapandam pakuburan maksudnya adalah setiap nagari harus mempunyai sebidang tanah yang dipergunakan sebagai pusat pemakaman bagi masyarakatnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga keteraturan dalam pengurusan anggota masyarakat yang meninggal dunia. Lazimnya, setiap suku di Minangkabau mempunyai pandam pekuburan masing-masing.
3. Aspek Kekeluargaan dalam Masyarakat107
Masyarakat hukum adat menjunjung tinggi hubungan genealogis dalam tatanan masyarakatnya. Demikian juga halnya dengan masyarakat hukum adat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau menghormati garis keturunan dalam bentuk suku. Jika
107 Hal ini dinyatakan dalam pepatah, nagari baampek suku, dalam suku babuah
paruik, dalam paruik ado ba jurai, dalam jurai bapariuak (nagari terdiri dari empat suku, dalam suku ada keluarga saparuik, dalam keluarga saparuik ada jurai, dalam jurai ada keluarga sapariuak). Julius Dt. Malako Nan Putiah, Mambangkik Batang Tarandam, 161. Pepatah ini menggambarkan tingkatan yang harus ada dalam pembentukan sebuah nagari di Minangkabau.
FORMALISASI NILAI ADAT MINANGKABAU ... | 159
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
diperhatikan hubungan kekeluargaan antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah nagari di Minangkabau, dapat dikelompokkan sebagai berikut: a. Kaampek suku. Sebuah nagari di Minangkabau minimalnya harus
terdiri dari 4 suku berbeda yang sudah mempunyai Penghulu
Andiko. Masyarakat hukum adat Minangkabau menganut paham eksogami-materilinial, dalam artian lain seorang laki-laki di Minangkabau tidak boleh menikah perempuan yang berasal dari kelompok suku asalnya sendiri.
b. Saparuik adalah keluarga besar yang berasal dari satu ibu dan berada dalam 4 generasi/keturunan (blood related). Setiap keluarga saparuik akan dipimpin oleh seorang mamak yang dituakan. Terkait dengan masalah hubungan tingkatan generasi dalam masyarakat hukum adat Minangkabau, dikenal beberapa istilah, sebagai berikut: 1) Samande (mande = ibu) merupakan anak-anak yang lahir dari
satu ibu kandung; 2) Sajurai merupakan keturunan yang berasal dari satu nenek dan
biasanya menempati satu rumah gadang dalam lingkungan rumah lainnya;
3) Saparuik merupakan keturunan yang berasal dari satu gaek yang sama (ibu dari nenek);
4) Sasuku, merupakan keturunan yang berasal dari satu niniek yang sama. Niniek menempati jenjang tertinggi dalam susunan kesukuan;
5) Sapayuang, bukan merupakan hubungan keturunan, hubungan sapayuang merupakan hubungan yang tercipta karena berada dalam satu kelompok kepemimpinan yang sama;
6) Sakampuang, hubungan yang tercipta karena kesamaan daerah tempat tinggal dalam kampuang, meskipun berbeda suku, dan;
7) Saparinduan merupakan hubungan keturunan yang berasal dari satu ibu kandung, meskipun dari bapak yang berbeda. Konsep ini mengorientasikan garis keturunan matrilinial dalam masyarakat hukum adat Minangkabau. Dalam masyarakat Minangkabau, seseorang bisa saja saparinduan dengan orang lainnya, namun berbeda bapak.
c. Tuo Kampuang merupakan seorang tokoh yang dituakan dalam sebuah kelompok keluarga saparuik yang semakin berkembang keturunannya. Tuo Kampuang mempunyai tugas mengurus harta pusaka di bawah pengawasan penghulu suku atau mamak kapalo
kaum. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa tuo kampuang
160 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
bertugas sebagai pembantu penghulu suku namun tidak mempuyai gelar sebagaimana layaknya seorang penghulu suku.
d. Tungganai adalah saudara laki-laki tertua dari ibu, sedangkan keseluruhan saudara laki-laki ibu disebut dengan mamak rumah. Tungganai mempunyai peranan vital dalam masyarakat hukum adat Minangkabau, baik dalam hubungan saparinduan ataupun hubungan antara mamak dengan kemenakan. Tungganai atau yang sering juga disebut dengan mamak kapalo waris berperan penting dalam menjaga dan mengurus harta pusaka dalam lingkungan sukunya. Nagari selaku pemerintahan terendah mempunyai beberapa
kewenangan. Penyerahan kewenangan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelengaraan pemerintahan daerah. Nagari dalam bentuknya sebagai bentuk pemerintahan asli pada tingkat terendah mempunyai kewenangan yang melingkupi urusan pemerintahan berdasarkan asal usul nagari yang sudah ada. Kewenangan ini berkaitan dengan tugas-tugas pembinaan dan pengembangan nagari sesuai dengan adat istiadat setempat. Dalam hubungannya dengan pemerintahan di tingkat kabupaten, nagari mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan urusan kabupaten yang diserahkan kepadanya. Demikian juga halnya dengan urusan-urusan yang diserahkan oleh pemerintah pada tingkat provinsi dalam konteks pembantuan. Nagari juga diserahi kewenangan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dengan syarat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.
Otonomi daerah di Sumatera Barat sepenuhnya tidak hanya bertumpu pada sistem pemerintahan nagari yang sudah ada. Namun lebih mengandalkan faktor relasi nagari selaku institusi lokal dengan kekuatan yang berada di luar dirinya sendiri. Institusi lokal selaku basis masyarakat mayoritas, apabila tidak ditransformasikan menjadi kekuatan yang demokratis, maka akan sangat sulit untuk membangun otonomi daerah yang sesungguhnya. Hal ini menunjukkan pentingnya peranan nagari dalam otonomi daerah sebagai upaya untuk mewujudkan proses demokratisasi.
Provinsi Sumatera Barat yang mengusung visi Otonomi Berbasis Nagari dalam bentuk usaha pemerintah daerah untuk menempatkan nagari pada posisi semula.108 Nagari diberikan kebebasan dalam membentuk
108 Permasalahan mendasar yang kemudian muncul dalam hal ini adalah
bagaimana menyamakan misi dalam menjalankan roda pemerintahan daerah. Dalam pelaksanaan otonomi berbasis nagari, tidak selalu misi-misi spesifik harus berada dalam
FORMALISASI NILAI ADAT MINANGKABAU ... | 161
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
tradisi. Nagari juga mempunyai wewenang dalam mengatur aktivitas anggota masyarakatnya sesuai dengan tatanan dan aturan yang disetujui oleh masyarakat tersebut. Setiap nagari mempunyai wewenang dalam menentukan karakteristik budaya lokal yang spesifik. Pengelolaan dan pengorganisasiannya diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing nagari. Sementara itu, urusan yang berkaitan dengan masalah-masalah adat berada dalam kompetensi absolut Kerapatan Adat Nagari.
Berdasarkan otonomi yang dimiliki nagari, maka pemerintahan nagari dapat mengembangkan peran serta masyarakat yang terorganisir dalam konsep suku secara demokratis dengan memanfaatkan budaya-budaya masyarakat Minangkabau. Peranan KAN dan atau lembaga keasyarakatan lainnya di nagari berfungsi sebagai mitra kerja dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan konsep inilah Pemerintah Daerah Sumatera Barat menetapkan nagari sebagai basis dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Secara sederhana dapat disebutkan bahwa otonomi daerah dibangun berdasarkan kemandirian pada level penyelenggaraan pemerintahan nagari.
Salah satu hal yang melatarbelakangi kembali ke bentuk pemerintahan nagari adalah karena banyaknya keterkaitan hubungan antar desa yang sudah ada, terutama pada tataran puak dan harta kekayaan nagari yang melampaui batas-batas desa. Pemerintahan desa dipilih oleh warga, demikian juga halnya dengan BPD. Tidak jauh berbeda dengan Dewan Pertimbangan Adat Nagari (DPAN) yang terdiri dari pemuka adat, tokoh agama, cadiak pandai (cendikiawan) dan tokoh perempuan. Di samping itu, Lembaga Adat Nagari (LAN) juga sudah dilembagakan dengan mengemban tugas utama untuk menjadi mediator dalam menyelesaikan sengketa harta kekayaan antar puak dan untuk melindungi adat secara umum. Jadi, ketika lembaga-lembaga tradisional berada dalam masa pemulihan fungsinya kembali, pada saat yang sama berbagai upaya untuk membatasi kekuasaan tokoh adat yang mempunyai kapasitas minim terus dilakukan.
Nagari mempunyai bentuk yang multi-fungsi dan multi-dimensi secara vertikal, horizontal dan kolateral. Secara vertikal, nagari merupakan bagian yang integral dalam pemerintahan nasional yang
satu koridor yang sama. Hal ini sesuai dengan ungkapan pepapat masyarakat Minangkabau, bahwa lain lubuak, lain ikannyo; lain padang, lain bilalang; lain nagari,
lain adatnyo (= lain lubuk, lain ikannya; lain padang, lain belalangnya; lain nagari, lain pula sistem adatnya).
162 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
berada pada hierarki terendah setingkat desa.109 Pemerintah nagari mewakili rakyat nagari dalam berhadapan dengan pemerintah nasional. Nagari merupakan sistem pemerintahan terendah yang melingkupi aspek formal dan informal. Aspek formal yang dimaksud adalah nagari merupakan bagian yang integral dalam sistem pemerintahan nasional. Sedangkan aspek informal adalah nagari merupakan unit kesatuan adat dan budaya dari masyarakat yang juga pada dasarnya adalah bagian integral dari kesatuan adat dan budaya Minangkabau. Nagari merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari alam Minangkabau. Kedua fungsi yang berbeda tersebut terpenuhi dan berjalan dalam kehidupan masyarakat nagari. Secara prinsip, tidak ada kontradiksi di antara keduanya. Hal ini dikarenakan keduanya mempunyai fungsi masing-masing yang sifatnya saling mengisi, melengkapi dan bahkan saling memperkaya. Secara kolateral, antara satu nagari dengan nagari lain yang bersebelahan dan dalam kesatuan wilayah adat yang sama mempunyai peran dan fungsi yang tidak sedikit. Secara formal memang dibatasi dalam bentuk dan nama sebuah nagari, namun setiap nagari yang berdekatan mempunyai kesamaan sejarah keturunan, adat istiadat dan lain sebagainya.
C. Sistem Pemerintahan dan Peran Lembaga Adat dalam Nagari
Pemerintahan nagari merupakan penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus kepentingan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat. Sebagai sistem pemerintahan terendah, maka pemerintahan nagari berlaku dan ditetapkan di seluruh kabupaten dan dapat ditetapkan di kota dalam Provinsi Sumatera Barat. Layaknya sebuah republik mini, nagari juga mempunyai lembaga legisatif dan lembaga eksekutif. Hanya saja dalam bidang yudikatif belum tersusun dan dicantumkan dalam bentuk regulasi yang mempunyai kekuatan hukum. Meskipun demikian, pada dasarnya peran lembaga yudikatif ini disandang oleh ninik mamak sebuah suku secara mandiri dan terlepas dari formalitas nagari. Penyelesaian sengketa adat, baik dalam kasus perdata atau pidana, sudah mulai menempuh jalur restorative justice.
109 Berbeda dengan desa, kedudukan nagari berdasarkan undang-undang
otonomi daerah dinyatakan bahwa nagari memiliki otonomi khusus dalam mengatur diri sendiri. Mochtar Naim, “Dengan ABSSBK”, 44.
FORMALISASI NILAI ADAT MINANGKABAU ... | 163
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
1. Pemerintah Nagari Selaku lembaga eksekutif dalam nagari, pemerintah nagari terdiri
dari wali nagari dan perangkat nagari. Perangkat nagari sendiri terdiri dari sekretaris nagari beserta beberapa perangkat lainnya. Perangkat lain tersebut terdiri dari pelaksana teknis lapangan, kepala urusan, unsur kewilayahan, kepala jorong
110 atau dengan sebutan lainnya. Posisi sekretaris nagari ditempati oleh seorang Pegawai negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Wali nagari adalah kepala pemerintahan dalam nagari yang dipilih langsung oleh warga masyarakat nagari. Wali nagari menjabat selama 6 (enam) tahun sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Prosedur untuk melakukan pemilihan wali nagari akan ditetapkan berdasarkan peraturan daerah pada tingkat kabupaten masing-masing.
Peran lembaga eksekutif dalam konteks pemerintahan nagari pada dasarnya merupakan posisi strategis. Sebagai kepala pemerintahan di Nagari, wali nagari bertugas untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMN) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang ditetapkan berdasarkan peraturan nagari. Wali nagari juga bertugas menyusun Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKPN) setiap tahunnya. Sebagai kepala pemerintahan pada daerah terendah dalam hierarki pemerintahan, wali nagari juga harus menyampaikan laporan kepada bupati/walikota melalui camat. Selain itu, wali nagari juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BAMUS (Badan Permusyawaratan Nagari).
2. Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari)
Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) merupakan bagian dari institusi nagari yang beranggotakan tokoh adat (ninik mamak), tokoh agama (alim ulama), cendikiawan (cadiak pandai) dan tokoh perempuan (bundo kanduang).111 Keanggotaannya ditentukan berdasarkan representasi masyarakat jorong yang dipilih dan ditetapkan
110 Jorong atau lazimnya juga disebut dengan Kampung merupakan wilayah
yang terdapat dalam nagari. Lihat penjelasan lebih lanjut dalam pasal 1 angka (8) Perda Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 jo. pasal 1 angka (10) Perda Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007
111 Perkembangan kedudukan perempuan dalam konteks masyarakat Minangkabau dapat ditemukan dalam Keebet von Benda-Beckmann, “Development, Law and Gender-Skewing: An Examination of The Impact of Development on The Socio-Legal Position of Indonesian Women, with Special Reference to Minangkabau”, Journal of Legal Pluralism, 30-31 (1990-1991): 87-120.
164 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
berdasarkan musyawarah dan mufakat. Masa jabatan BAMUS Nagari adalah 6 tahun dan kemudian dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya. BAMUS Nagari dipimpin oleh seseorang yang ditunjuk dari dan oleh anggota BAMUS Nagari itu sendiri.112 Keanggotannya diharuskankan berjumlah ganjil, minimal 5 (lima) orang dan maksimal adalah 11 (sebelas) orang. Jumlah anggota BAMUS Nagari berbeda-beda pada tiap nagari karena ditentukan berdasarkan luas wilayah, representasi anggota masyarakat dan kemampuan finansialnya.
BAMUS Nagari mempunyai beberapa tugas yang berkaitan dengan kelangsungan pemerintahan nagari. Selaku representasi dari anggota masyarakat, BAMUS Nagari menerima laporan pertanggungjawaban dai wali nagari. Dalam menetapkan peraturan nagari, seorang wali wali nagari harus mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota BAMUS Nagari. BAMUS Nagari bersama wali nagari menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) setiap tahunnya berdasarkan peraturan nagari. BAMUS Nagari juga mempunyai kewenangan dalam menyetujui penerimaan bantuan terhadap nagari. Dalam hubungan antar nagari, BAMUS Nagari memberikan persetujuan dan secara bersama-sama mengurus kepentingan antar nagari. BAMUS Nagari juga bertugas mengawasi pengalihan kekayaan nagari bersama dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan masyarakat nagari.
Pada dasarnya, konsep kepemimpinan di Minangkabau mengenal konsep pepaduan tiga unsur utama dalam masyarakat yang digambarkan dalam adagium tungku tigo sajarangan, tali tigo sapilinan. Ketiga unsur tersebut adalah ninik mamak (penghulu), alim ulama (tokoh agama) dan cadiak pandai (cendikiawan). Ketiga unsur ini merupakan sebuah kesatuan dalam sistem kepemimpinan dalam Minangkabau. Masing-masing unsur terhubung dengan aspek yang menjadi kewenangannya. Kepemimpinan masyarakat Minangkabau memegang peranan penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat dan mendorong keberhasilan generasi selanjutnya. Arus perubahan zaman merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat dielakkan. Demikian juga halnya dengan berlakunya regulasi otonomi daerah. Keberadaan Perda Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 jo Nomor 2 Tahun 2007 merupakan bentuk modernisasi sistem kepemimpinan dalam masyarakat hukum adat Minangkabau.
112 Dalam penjelasan pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor
2 Tahun 2007 dinyatakan bahwa kepemimpinan BAMUS Nagari terdiri dari satu orang ketua dan satu orang wakil yang dipilih secara langsung oleh anggota BAMUS Nagari dalam rapat yang diadakan secara khusus untuk itu.
FORMALISASI NILAI ADAT MINANGKABAU ... | 165
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
3. Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kerapatan Adat Nagari merupakan lembaga kerapatan ninik
mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako. KAN berkedudukan sebagai lembaga musyawarah masyarakat adat tertinggi dalam lingkungan masyarakat. KAN mempunyai hubungan koordinasi sekaligus menjadi lembaga konsultasi bagi aparat pemerintah nagari dalam membentuk berbagai peraturan nagari dan pengelolaan harta kekayaan nagari. KAN mempunyai hubungan mitra sejajar dengan wali nagari dalam menjalankan pemerintahan.113 Dalam menjalankan fungsinya, KAN dibantu oleh alim ulama dan cadiak pandai. KAN juga mempunyai fungsi dan peran penting dalam upaya pemekaran, penggabungan dan penghapusan nagari. Keterlibatan KAN dalam fungsi ini harus didasarkan pada asas musyawarah dan mufakat menurut alua jo patuik (alur dan kepatutan) sepanjang tidak bertentangan dengan adat basandi syarak,
syarak basandi Kitabullah. Bagi masyarakat Minangkabau, keberadaan KAN masih dapat
ditempatkan dalam kerangka peraturan perudang-undangan. Keberadaannya tidak hanya terakomodasi dalam Perda Nomor 2 Tahun 2007 saja, namun juga diakui dalam Perda Nomor 13 Tahun 1983. Adanya pengakuan dalam Perda Nomor 13 Tahun 1983 ini memungkinkan adanya pengakuan terhadap nagari sebagai komunitas masyarakat adat pada masa Orde Baru dan pengakuan KAN sebagai lembaga yang mewakili komunitas-komunitas ini.114 Berbagai peraturan pelaksana yang mengikutinya memberikan instruksi-instruksi terperinci untuk konstitusi KAN dan bagaimana KAN dalam bertugas dalam mempertahankan nilai-nilai tradisional, mempertahankan populasi nagari, menyelesaikan sengketa-sengketa yang terkait dengan masalah-masalah adat serta mengelola harta kekayaan nagari.
Keberadaan KAN yang ditugaskan untuk memelihara kelestarian adat dan menyelesaikan sengketa sako dan pusako, mengindikasikan bahwa KAN merupakan lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa adat.115 Penyelesaian perkara pidana melalui lembaga adat
113 Penjelasan lebih lanjut bisa disimak dalam Anggaran Dasar (AD) Lembaga
Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) pasal 12 ayat 6 terkait tugas pokok dan fungsi KAN selaku pucuak undang.
114 Franz and Keebet von Benda-Beckmann, “Identitas-identitas Ambivalen”, 547.
115 Pada prinsipnya, hukum adat tidak membedakan antara sengketa perdata dan pidana. Maka dalam kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa adat, KAN juga
166 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
mempunyai urgensi tertentu jika dikaitkan dengan adanya ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan formal, khususnya dalam penyelesaian perkara pidana yang mempunyai muatan dan dimensi adat di dalamnya. Masyarakat hukum adat tidak akan merasa puas karena putusan pengadilan belum mampu mengembalikan keseimbangan magis yang timbul sebagai akibat adanya sebuah pelanggaran yang terkaitan dengan nilai-nilai adat.
Franz von benda-Beckmann116 pernah melakukan penelitian dan analisis terhadap bentuk peradilan tradisional ini dan melakukan komparasi antara peradilan tradisional yang terdapat di Minangkabau dengan Shonaland di Afrika. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peradilan pribumi yang tidak dikenal dalam hierarki sistem peradilan nasional pada dasarnya lebih efisien dalam menyelesaikan sengketa pada tingkat terendah seperti nagari di Minangkabau. Menanggapi kondisi tersebut, ilmu hukum menawarkan sebuah konsep yang diyakini dapat menyelesaikan masalah kesenjangan rasa keadilan hukum dalam masyarakat hukum adat. Konsep yang ditawarkan tersebut adalah institusi restorative justice. Restorative justice dapat diartikan sebagai sebuah konsep pemikiran yang merespon117 pengembangan sistem peradilan pidana dengan menintikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang seringkali merasa tersisihkan dengan mekanisme sistem pidana saat ini.118 Secara sederhana, restorative justice dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa pidana secara damai di luar pengadilan. Penyelesaian perkara dalam kerangka restorative justice bertujuan untuk melindungi kepetingan pelaku tanpa merugikan pihak berwenang dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana adat. Elwi Danil, “Peluang Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana” (Makalah yang dipresentasikan dalam Musyawarah Adat: Aplikasi Manjemen Suku dan Pemberdayaan Hukum Adat dalam Hukum Nasional, Solok, 23 Maret 2012), 9.
116 Hasil penelitian tersebut disampaikan pada The Tagung für Rechtsvergleichung yang diadakan oleh The Deutsche Gesselschaft für Rechtsvergleichung di Lausanne, Switzerland pada tanggal 14 September 1979. Untuk penjelasan lebih lanjut bisa disimak dalam Franz von Benda-Beckmann, “Some Comments On The Problems Of Comparing The Relationship Between Traditional And State Systems Of Administration Of Justice In Africa and Indonesia”, Journal of Legal
Pluralism, 12 (1981): 165-175. 117 Kemunculan pemikiran restorative justice merupakan manifestasi kritik atas
penerapan sistem peradilan pidana dengan konsep penghukuman yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan berbagai konflik sosial. Ketidakefektivan tersebut diakibatkan karena pihak yang terlibat dalam konflik tidak diikutkan dalam penyelesaian konflik.
118 Eva Achjani Zulfa, Pergeseran Paradigma Pemidanaan (Bandung: Lubuk Agung, 2011), 65.
FORMALISASI NILAI ADAT MINANGKABAU ... | 167
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
korban. Penyelesaian perkara pidana selama ini cenderung bersifat retributif (pembalasan), utilitarian dan rehabilitatif (memperbaiki). Sementara itu, penyelesaian perkara berdasarkan konsep restorative
justice dilakukan berdasarkan musyawarah dan mediasi untuk memulihkan keseimbangan dengan melibatkan anggota keluarga pelaku, anggota keluarga korban dan pihak masyarakat. Jadi, penyelesaian sengketa dialihkan dari pihak peradilan sebagai wakil negara ke pihak masyarakat yang dalam hal ini diakomodir oleh KAN.
Dalam menjalankan tugas selaku lembaga yang bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian adat istiadat, di samping KAN dikenal juga sebuah Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM). LKAAM merupakan sebuah lembaga sosial yang mewakili kepentingan masyarakat hukum adat Minangkabau. Idealnya, LKAAM merupakan wadah penyaluran aspirasi komunitas adat dalam hubungannya dengan pelestarian nilai-nilai adat dalam masyarakat Minangkabau. LKAAM sebagai lembaga yang mewadahi ninik mamak dan pemuka adat pada dasarnya tidak termasuk dalam struktur kepemimpinan tradisional di Minangkabau.
Pembentukan LKAAM bukanlah karena adanya prakarsa dari masyarakat. LKAAM didirikan pada tahun 1966 setelah Soeharto berkuasa. Pada awal berdirinya, lembaga ini terlibat dalam politik Partai Golkar.119 Meskipun demikian, menjelang berakhirnya rezim pemerintahan Soeharto, LKAAM mulai menjauhkan diri dari Golkar dan mengambil sikap independen. Sebagai sebuah organisasi bentukan pemerintah, dalam Anggaran Dasarnya dicantumkan bahwa LKAAM bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai luhur adat Minangkabau yang terpatri dalam konsep adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.
119 Penjelasan lebih lanjut dapat ditemukan dalam Gerry van Klinke,
“Kembalinya Para Sultan: Pentas Gerakan Komunitarian Dalam Politik Lokal” dalam Adat dalam Politik Indonesia, eds. Jamies E. Davidson, et. all. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), 176. Prakarsa untuk mewadahi ninik mamak dan penghulu adat dalam organisasi LKAAM oleh kalangan militer di awal Orde Baru sebenarnya lebih didorong oleh keinginan untuk menjauhkan dan membersihkan para penghulu adat yang terlibat dengan kegiatan Partai Komunis. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan apabila kemudian LKAAM mempunyai sebuah kedekatan hubungan dengan pemerintahan dan kalangan ABRI. Hal ini juga terlihat dalam tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya. Pada masa tersebut, Ketua LKAAM dijabat oleh Baharuddin Dt. Rangkayo Basa yang juga menjabat sebagai Kepala Jawatan Penerangan Sumatera Barat. Sementara itu, kapten Safroedin Bahar (Perwira Kodam) yang sekaligus Ketua DPD Golkar juga duduk dalam sekretariat LKAAM itu sendiri. Dengan demikian, tidaklah mengherankan jika pada masa awal berdirinya LKAAM merupakan bentuk perpanjangan tangan Pemerintah dan Golkar di tingkat daerah.
168 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Selaku organisasi kemasyarakatan yang berorientasi kultural, maka wilayah kerja LKAAM tidak mengikuti seluruh wilayah kultural Minangkabau, akan tetapi bertitik tolak dari batasan wilayah territorial Sumatera Barat. Induk organisasi ini berada di ibukota provinsi dan secara hierarkis mempunyai cabang pada tingkat kabupaten dan kecamatan. Sementara itu, di dalam nagari dikenal adanya KAN yang mempunyai tugas dan wewenang yang sama dengan LKAAM. Meskipun demikian, tidaklah berarti bahwa KAN merupakan bagian LKAAM. Antara KAN dengan LKAAM hanya mempunyai hubungan konsultatif terkait dengan program-program yang hendak dilaksanakan pada tingkatan nagari. KAN yang mempunyai fungsi dan kedudukan yang jelas pada nagari-nagari bersangkutan, merupakan sebuah organisasi independen pada tingkat nagari. Hal ini terkait dengan logika dalam konsep adat salingka nagari, sehingga tidak ada organisasi penghulu lainnya di atas KAN.
D. Finansial & Hak Ulayat Nagari
Pembahasan mengenai finansial nagari tidak terlepas dari pembahasan mengenai harta kekayaan nagari dan ulayat nagari. Harta kekayaan nagari adalah harta benda yang telah ada atau yang kemudian menjadi milik dan kekayaan nagari baik bergerak ataupun tidak bergerak. Sedangkan ulayat nagari adalah harta benda dan kekayaan nagari di luar ulayat kaum dan suku yang dimanfaatkan untuk kepentingan anak nagari. Harta kekayaan nagari meliputi pasar nagari, tanah lapang atau tempat rekreasi nagari, balai, mesjid atau surau nagari, tanah, hutan, sungai, kolam atau laut yang menjadi ulayat nagari, bangunan yang dibuat pemerintah nagari atau anak nagari untuk kepentingan umum dan harta benda serta kekayaan lainnya.
Kajian mengenai hak ulayat dalam adat seringkali diidentikkan dengan tenurial adat.120 Secara sederhana, tenurial dapat diartikan dengan segala sesuatu yang bersifat atau berhubungan dengan kepemilikan atau penggunaan tanah. Tenurial adat merupakan suatu sistem yang berhubungan dengan tanah. Sistem tersebut berisikan suatu perangkat
120 Term tenurial berasal dari kosakata bahasa inggris, tenure yang berarti
period, time, condition of holding or using land (periode, waktu, syarat-syarat kepemilikan atau pemanfaatan tanah). A.S. Hornby, Oxford Advanced Learner’s
Dictionary of Current English (Oxford: Oxford University Press, 1987), 891. Pada dasarnya, term tenurial merupakan terminologi yang dikenal dalam sistem hukum anglo
saxon (common law system). Sementara itu, dalam sistem hukum eropa continental (civil
law system), terminologi yang sama dikenal dengan hubungan hukum (rechtsbetrekking) antara orang dengan tanah atau yang lazim dikenal dengan hak kebendaan.
FORMALISASI NILAI ADAT MINANGKABAU ... | 169
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
kepentingan atas tanah dalam masyarakat yang dinyatakan dan dijadikan sebagai alasan orang memiliki tanah. Hubungan tersebut terbentuk dalam setiap masyarakat. Sistem ini ditentukan berdasarkan hukum yang tidak tertulis atau hukum adat (unwritten and/or costumary law) dan sangat dipengaruhi oleh budaya, agama, sistem politik, dan pembangunan masyarakat.121 Perbedaan kepentingan atas tanah biasanya ditentukan oleh hukum tanah.122 Implikasinya, pemberlakuan hukum tanah berbeda-beda di setiap wilayah dan kesatuan masyarakat yang terkait.
Pemanfaatan dan pengelolaan harta kekayaan nagari dilaksanakan oleh pemerintah nagari dengan didasarkan kepada peraturan nagari. Peraturan nagari dibentuk dan ditetapkan oleh wali nagari dengan adanya persetujuan dari BAMUS Nagari. Selain didasarkan kepada peraturan nagari, dalam mengelola dan memanfaatkan harta kekayaan nagari, pemerintah nagari juga diharuskan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan KAN. Harta kekayaan nagari yang dikelola oleh pihak lain, setelah masa pengelolaannya berakhir harus dikiembalikan kepada nagari, dengan kata lain setiap kemungkinan perpanjangan perjanjian dengan pihak ketiga harus dilakukan bersama dengan pihak nagari. Sementara itu harta kekayaan nagari yang dikelola oleh pemerintah, pemanfaatannya harus memperhatikan kepentingan nagari.
Guna menjamin berjalannya pemerintahan pada tingkat nagari, nagari juga diharuskan mempunyai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari). APB Nagari terdiri dari bagian pendapatan nagari, belanja nagari dan pembiayaan. Rancangan APB Nagari dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan nagari yang ditetapkan secara bersama oleh wali nagari dan BAMUS Nagari setiap tahunnya berdasarkan peraturan nagari. Pendapatan dan penerimaan nagari meliputi pendapatan asli nagari, penerimaan bantuan dari pemerintah daerah dan penerimaan lainnya. Pendapatan asli nagari terdiri dari; hasil kekayaan nagari; hasil usaha nagari; retribusi nagari, terutama retribusi asli yang sudah ada di nagari; hasil swadaya dan sumbangan masnyarakat; hasil gotong royong dan pendapatan asli lainnya yang sah. Sementara itu penerimaan bantuan dari pemerintah daerah meliputi; bagi hasil dari pajak daerah minimalnya 10% untuk nagari dan sebagian dari retribusi daerah; bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima
121 J. Zevenbergen, “System of Land Registration: Aspects and Effects” (PhD
Thesis Technische Universiteit Delf, 2002), 2-11. 122 Kurnia Warman, “Kajian Hukum Tentang Peluang dan Kendala Bagi
Kebijakan Daerah Dalam Penguatan Tenurial Adat”, dalam Potret Pengelolaan Hutan di
Nagari, ed. Didin Suryadin (Padang: HuMa, 2007), 1.
170 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
pemerintahan kabupaten/kota minimalnya 10% dengan ketentuan pembagian yang proporsional bagi setiap nagari; pembiayaan atau pelaksanaan tugas pembantuan; bantuan lainnya dari pemerintah pusat dan daerah dan bagian dari bagi hasil dari dana yang dipungut pemerintah dari nagari. Sedangkan penerimaan lainnya meliputi pinjaman nagari, hasil kerjasama dengan pihak lain dan pendapatan lainnya yang sah.
Untuk meningkatkan perekonomian dalam nagari, pemerintah nagari berhak membentuk Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nagari) yang berkedudukan di nagari dan membuka cabang di daerah rantau. Dalam pedoman pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari tidak mengatur hal-hal yang mengakibatkan terjadinya usaha monopoli dalam nagari. Demikian juga halnya dengan pengembangan perekonomian anak nagari dapat dilakukan dengan penghimpunan modal yang mengerahkan potensi yang ada di nagari dan di rantau.
Kajian mengenai harta kekayaan nagari dan hak ulayat nagari merupakan bagian terpenting dalam konsep nagari. Pembahasan keduanya tidak dapat dipisahkan dengan konsep pengembangan SDA dalam nagari serta hubungannya dengan pemerintah pusat. Keberadaan perda nagari secara teoritisnya memang dapat menstimulus penyatuan desa menjadi nagari, namun belum dapat melebur sistem adat yang berbasis ninik mamak dengan sistem pemerintahan modern. Hal ini disebabkan adanya pemisahan tidak langsung antara pemerintahan nagari yang dikepalai oleh seorang wali nagari yang dipilih langsung oleh masyarakat dengan kepemimpinan KAN yang merupakan konsorsium ninik mamak yang direkrut berdasarkan mekanisme adat.
Masalah ulayat menjadi satu hal yang sentral dalam diskusi-diskusi mengenai peranan adat dalam struktur nagari yang baru, karena klaim-klaim atas tanah yang diarahkan terhadap negara atau para investor harus didasarkan pada adat, atas nama nagari, para pemimpin klan dan garis keturunan.123 Fungsi tanah ulayat dapat dipahami dari 3 dimensi, yaitu: dimensi sosial budaya, dimensi sosial ekonomi dan dimensi jaminan sosial. Fungsi dalam dimensi sosial budaya merupakan fungsi dan penataan tanah ulayat oleh masyarakat hukum adat yang terkait erat dengan sistem kekerabatan. Hal ini disebabkan karena tanah ulayat dianggap sebagai unsur perekat antar warga masyarakat hukum adat dan antara nasyarakat hukum adat dengan unsur kepemimpinannya. Menurut
123 Franz and Keebet von Benda-Beckmann, “Identitas-identitas Ambivalen”, 553.
FORMALISASI NILAI ADAT MINANGKABAU ... | 171
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Benda-Beckmann, sebagaimana yang dikutip oleh Alidinar Nurdin,124 tanah ulayat di Minangkabau pada prinsipnya dapat berfungsi sebagai salah satu pilar dalam kosepsi masyarakat hukum adat. Pilar-pilar pembentuk masyrakat hukum adat tersebut adalah susunan masyarakat yang sudah mapan, memiliki harta sendiri dan pemerintahan sendiri. Tanah ulayat secara anatomi dapat diibaratkan sebagai daging yang melindungi tulang dalam kerangka tubuh manusia. Tulang belulang tersebut merupakan sebuah sistem hubungan kekerabatan. Hubungan antar sesama masyarakat hukum adat dengan hubungannya dengan pemimpinnya sudah begitu mapan dengan keberadaan tanah ulayat. Kondisi ini akan berbanding terbalik apabila authority atau kewenangan untuk menata penggunaan tanah dan kekayaan alam yang terdapat dalam daerah teritorial masyarakat hukum adat sudah hilang. Suksesi tanah ulayat sebagai salah satu kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat menjadi sangat signifikan karena mempunyai kaitan yang sangat erat dengan sistem matrilineal125 yang dianut masyarakat hukum adat Minangkabau.
Fungsi tanah ulayat dalam dimensi sosial ekonomi adalah menjadikan warga masyarakatnya hidup sejahtera lahir batin. Masyarakat hukum adat didorong untuk membangun hubungan ekonomi dengan keberadaan tanah ulayat mengutamakan efektivitas penggunaan lahan. Menurut aspek sosial ekonomi ini juga tanah ulayat berpeluang untuk dijaminkan atau dibebani hak tanggungan.126 Berdasarkan dimensi jaminan sosial, tanah ulayat merupakan representasi dari model jaminan sosial tradisional. Model jaminan sosial ini lebih efektif berlaku jika pada suatu kondisi pemerintah tidak mampu memberikan jaminan sosial kepada masyarakatnya. Tanah ulayat diharapkan dapat memenuhi kepentingan umum untuk generasi saat ini dengan tidak mengabaikan
124 Alidinar Nurdin, “Pentingnya Tanah Ulayat dalam Otonomi Nagari di
Provinsi Sumatera Barat” (Makalah yang dipresentasikan dalam Musyawarah Adat: Aplikasi Manajemen Suku dan Pemberdayaan Hukum Adat dalam Hukum Nasional, Solok 23 maret 2012), 9-10.
125 Tanah ulayat di Minangkabau tidak dapat dipisahkan dari sistem kekerabatan matrilineal yang mengambil garis keturunan dari pihak ibu. Hal ini digambarkan dalam pepatah, basuku babakeh ibu, babangso babakeh ayah, jauah
mancari induak, dakek mancari suku (mempunyai suku dari garis ibu, mempunyai bangsa dari garis ayah, meskipun susah mencari orang tua kandung, namun suku merupakan kekerabatan terdekat).
126 Kondisi ini digambarkan melalui pepatah, abih kato adat, cari kato
mufakaik; abih adat dek bakarilaan, abih kato dek mufakaik (sesuatu yang tidak ditemukan dalam adat bisa diselesaikan melalui musyawarah mufakat; penggunaan konsepsi di luar adat berdasarkan prinsip kerelaan melalui upaya mufakat).
172 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
generasi yang akan datang. Oleh sebab itu, tanah ulayat harus dijaga kelestariannya melalui penataan, penggunaan, pemanfaatan dan pencadangan dalam bentuk penggunaan tanah ulayat sesuai porsi yang proposional.
Konsepsi pengelolaan hutan merupakan konsepsi komunalistik yang didasari kepada konsepsi penguasaan ulayat atas sumberdaya alam. Konspesi ulayat merupakan penguasaan sumberdaya alam secara komunal dari susunan masyarakat yang kolektif. Konsepsi tahan ulayat bersifat holistik, baik pada ruang tanah, hutan, air, danau dan laut.127 Berdasarkan asal usul tanah ulayat, masyarakat nagari sangat berkepentingan terhadap tanah ulayat. Penghulu sebagai pemegang wewenang terhadap tanah ulayat, anak kemenakan, penduduk pendatang (transmigran), pemerintah dan pihak investor sebagai pengambil manfaat dari tahan ulayat.128 Kajian terhadap harta kekayaan nagari dan ulayat nagari juga terkait dengan Perda Tahan Ulayat. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, Perda Nagari menyatakan bahwa ulayat nagari merupakan bagian dari kekayaan nagari dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah nagari harus melakukan konsultasi dengan KAN. Sedangkan dalam Perda Tanah Ulayat disebutkan bahwa tanah ulayat dikuasai oleh ninik mamak di nagari yang tergabung dalam KAN.
Penataan, penggunaan pemanfaatan dan pencadangan lahan secara politis tradisional bertujuan untuk menjaga keadilan, keserasian dan keseimbangan.129 Menjaga keadilan ditujukan untuk menjaga kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat hukum adat untuk mendapatkan sebidang tanah ulayat sesuai dengan kebutuhannya. Apabila tidak ada keadilan dalam hal peluang pemilikan tanah ulayat, dikhawatirkan akan terjadi monopoli pemilikan dan pemanfaatan tanah ulayat oleh pihak-pihak tertentu. Keserasian merupakan upaya menciptakan hubungan yang harmonis antar sesama warga masyarakat hukum adat serta hubungan dengan pemimpinnya, dalam hal ini adalah ninik mamak guna
127 Hutan dipandang sebagai pengikat dan penanda kolektivisme serta media
untuk mempertahankan ikatan kekerabatan. Nurul Firmansyah, “Eksistensi Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat Nagari: Catatan Kecil Pengalaman Advokasi di Nagari Kambang, Nagari Guguk Malalo dan Nagari Simanau”, dalam Potret Pengelolaan
Hutan di Nagari (Padang: HuMa, 2007), 63-64. 128 Pada prinsipnya, tanah ulayat di Minangkabau hanya boleh digarap dan
dimanfaatkan saja tanpa pemindahan hak kepemilikan. Kondisi ini digambarkan dalam pepatah aianyo buliah diminum, buahnyo bualiah dimakan, kabau tagak kubangan
tingga (airnya boleh diminum, buahnya boleh dimakan, kerbau yang sudah selesai berendam meninggalkan kubangannya).
129 Alidinar Nurdin, “Pentingnya Tanah Ulayat”, 8.
FORMALISASI NILAI ADAT MINANGKABAU ... | 173
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
terbentuknya kesatuan yang integral dalam sebuah nagari. Keseimbangan merupakan upaya penciptaan lingkungan kehidupan yang nyaman, indah, tertib serta terhindar dari bencana alam. Konsep keseimbangan pada dasarnya berhubungan dengan efektivitas pemanfaatan130 tanah ulayat serta porsi yang proporsional sehingga menjamin keseimbangan dengan tidak atau meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan.
Terkait dengan pemanfaatan tanah ulayat sebagaimana yang dibahas dalam Perda Nagari, Perda Tanah Ulayat telah mempunyai pengaturan tentang mekanisme-mekanisme pemanfaatan tanah ulayat dalam 3 mekanisme. Pertama, pemanfaatan tanah ulayat oleh anggota masyarakat adat (nagari) melalui mekanisme internal nagari berdasarkan hukum adat yang berlaku pada masing-masing daerah tersebut. Kedua, mekanisme pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan umum diharuskan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 jo Nomor 65 Tahun 2005. Ketiga, mekanisme pemanfaatan tanah ulayat oleh pihak ketiga (investor) melalui perjanjian kerjasama atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan disarankan dalam bentuk bagi hasil penyertaan modal, dalam hal ini tanah ulayat dianggap sebagai modal (saham). Perda Tanah Ulayat juga menyebutkan bahwa tanah-tanah yang telah dimanfaatkan untuk investasi agar dikembalikan ke bentuk semula. Penggunaan klausul kembali ke bentuk semula menunjukkan upaya pemulihan hak ulayat pada tanah yang telah dimanfaatkan sebelum perda ini ditetapkan.
130 Masyarakat hukum adat Minangkabau mempunyai kerangka acuan dalam
upaya efektivitas pemanfaatan tanah, sebagaimana yang tergambar dalam pepatah, nan
data ka parumahan, nan baraia ka sawah, nan lereang ka ladang, nan tunggang ka
hutan, gurun ka tampek pusaro, tanjuang dijadian paninjauan (bidang tanah yang datar dimanfaatkan untuk perumahan, bidang tanah yang lembab dan basah dijadikan lokasi sawah, bidang tanah pada lereng dijadikan ladang, bidang tanah yang keras dijadikan hutan, bidang tanah yang kering dijadikan lokasi pemakaman).
174 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Matriks 4.1. Perkembangan Pemerintahan Nagari dan Penguasaan Ulayat Nagari
Di Sumatera Barat Sejak kemerdekaan Hingga Reformasi
No Periode Pemerintahan (Dasar Hukum)
Pelaksana Pemerintahan Nagari
Kerapatan Adat Nagari Penguasaan Tanah Ulayat
1.
1946 – 1950 Maklumat Residen
Sumatera Barat No. 20/1946
- Walinegeri
- Dewan Perwakilan Negeri
- Dewan Harian Negeri
Tidak diatur dan tidak dilibatkan
dalam pemerintahan
nagari
Tidak jelas
2.
1950 – 1963 Peraturan Daerah Sumatera Tengah No. 50/GP/1950
- Kepala Wilayah - Dewan Perwakilan
Rakyat Wilayah
Tidak diatur dan tidak dilibatkan
dalam pemerintahan
nagari
Tidak jelas
3.
1963 – 1968
SK Gubernur
Sumatera Barat
No. 2/Desa/GSB/Prt-1963
- Kepala Nagari
- Badan Musyawarah Nagari
- Musyawarah Gabungan
Tidak diatur dan tidak dilibatkan
dalam pemerintahan
nagari
Menjadi kewenangan Pemerintah Nagari dan dijelaskan dalam bentuk: bunga kayu, bunga pasir, bunga batu
dan bunga karang
FORMALISASI NILAI ADAT MINANGKABAU ... | 175
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
4.
1968 – 1974 SK Gubernur
Sumatera Barat No. 015/GSB/1968
- Wali Nagari - DPR Nagari
Dibantu oleh Kerapatan Nagari sebagai :
- Peradilan agama dan adat
- Penasehat pemerintah nagari
Tidak diatur dan tidak dilibatkan
dalam pemerintahan
nagari
Pemerintah nagari berwenang dalam memelihara kekayaan nagari,
berdasarkan SK Gubernur Sumbar No. 80/GSB-1972 tentang keuangan
nagari, sebagai berikut : - Retribusi hasil hutan (kayu, damar,
rotan dan lain sebagainya) - Retribusi karet rakyat
- Bunga pasir, batu, karang (hasil laut, danau, sungai dan lain
sebagainya) - Retribusi hasil bumi lainnya (cengkeh, cassia vera dan lain
sebagainya)
5.
1974 – 1981 SK Gubernur
Sumatera Barat No. 155/GSB-1974
- Wali nagari - Kerapatan Nagari
Tidak diatur dan tidak dilibatkan
dalam pemerintahan
nagari
Pemerintah nagari berwenang untuk memelihara harta benda nagari berupa pasar, tanah lapang atau
tempat rekreasi, mesjid atau surau, tanah, hutan, sungai, kolam dan laut sebagai ulayat nagari, bangunan dll
6. 1981 – 2000
Era Pemerintahan Desa Perda No. 7/1981
- Kepala Desa - Lembaga
Musyawarah Desa (LMD)
Kerapatan Adat Nagari
(KAN) dibentuk
berdasarkan
Pemerintahan nagari dihapus dan kewenangannya dilimpahkan kepada
KAN untuk menginventrarisir, menjaga, mengurus dan
memanfaatkan kekayaan nagari
176 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Dibantu oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat
Desa (LKMD)
Perda Nomor 13 / 1983
untuk kesejahteraan masyarakat nagari. Dilakukan penyerahan
kekayaan nagari dari bekas wali nagari kepada Ketua KAN
7. 2000 – sampai sekarang
Perda No. 9/2000 jo Perda No. 2/2007
- Wali Nagari - Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN)
yang kemudian diubah menjadi Badan
Permusyawaratan Nagari (BAMUS
Nagari) Dibantu oleh:
- Badan Musyawarah Adat dan Syarak (BMAS) Nagari
- Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM)
Lembaga Adat Nagari (LAN),
KAN yang berkaitan
dengan sako dan pusako di
nagari
Penguasaan tanah ulayat dikembalikan kepada nagari.
Sementara itu, secara de facto tanah ulayat nagari masih dikuasai oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN)
BAB V DAMPAK PENERAPAN NILAI ADAT DALAM
SISTEM PEMERINTAHAN NAGARI DI MINANGKABAU TERHADAP PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Bab ini mengkaji dampak dari implementasi nilai-nilai adat tradisional Minangkabau terhadap perkembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dianalisis dari empat faktor, yaitu: pemekaran wilayah dan peningkatan pelayanan publik (public service), indeks pembangunan manusia (welfare state), penyelesaian sengketa dan partisipasi tokoh adat dalam pembangunan. Pengukuran implementasi ini menggunakan kerangka acuan yang sudah ditetapkan oleh Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah (PKKOD) pada tahun 2006. A. Pemekaran Wilayah dan Peningkatan Pelayanan Publik
Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada uraian sebelumnya, secara tradisional, masyarakat hukum adat Minangkabau hidup berkelompok dalam suatu ikatan genealogis dan teritorial yang otonom dengan sistem pemerintahan yang kolektif berdasarkan kepada hukum adat.1 Kondisi ini berlangsung sejak masa pra kolonialisme. Sebelum terjadinya perang paderi, Minangkabau berada dalam kesatuan luhak dan rantau yang terdiri dari nagari-nagari. Setiap nagari mempunyai kebebasan secara adat. Nagari selaku volkgemeenschap genealogis
1 Nuraini Budi Astuti, et. all., “Dilema Dalam Transformasi Desa Ke Nagari:
Studi Kasus di Kenagarian IV Koto Palembayan Provinsi Sumatera Barat”, dalam Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia, Vol-3, No. 2 (2009): 153. Lihat juga dalam Keebet von Benda-Beckman, Goyahnya Tangga Menuju
Mufakat (Jakarta: Grasindo, 2000), 67.
178 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
teritorial sudah diakui eksistensinya sejak lama.2 Kedatangan Belanda ke Indonesia mempengaruhi sistem tradisional ini. Secara sistematis dan bertahap, Belanda mulai ikut campur dalam sistem pemerintahan nagari. Hal ini terbukti dengan adanya Regering Reglement (RR) pada tahun 1854 berdasarkan Staatsblad 1854 Nomor 129. Kedudukan nagari sebagai sebuah lembaga yang otonom juga diakui berdasarkan perjanjian Plakat Panjang tahun 1833. Berbagai regulasi kemudian ditetapkan guna menunjang kepentingan kolonialisme Belanda di Indonesia dengan tetap mempertahankan kedudukan otonomi pada tingkat daerah.
Berbeda dengan masa Belanda, pemerintah pendudukan Jepang3 tidak menggunakan konsep otonomi. Jepang tetap mengakui keberadaan daerah kabupaten dan kotapraja dengan kekuasaan yang dilaksanakan oleh kentyoo dan sentyoo. Hal ini menunjukkan bahwa tipikal pemerintahan yang diterapkan Jepang hanya bersifat dekonsentrasi belaka atau yang juga dikenal dengan istilah ambtelijke decentralitatie.4 Sampai pada masa ini, tidak diketahui secara pasti jumlah otoritas pemerintahan pada tingkat nagari.
Proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak begitu mempengaruhi kondisi otonomi pemerintahan nagari di Minangkabau. Otonomi pada tingkat nagari hilang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1954. Keputusan Presiden ini mengamanatkan untuk menghidupkan kembali wilayah pemerintahan berdasarkan Peraturan Pembentukan Kotamadya Untuk Di Luar Wilayah Jawa dan Madura (IGOB) tahun 1938. Keputusan ini juga menegaskan bahwa sistem demokrasi yang berlaku di nagari adalah demokrasi modern, bukanlah demokrasi adat lagi. Secara umum, administrasi yang berlaku di Sumatera Barat adalah pemerintahan yang berada di bawah jorong. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1977, Pemerintahan Daerah
2 Sri Natin, “Perubahan Sosial Kedudukan dan Peran Mamak Terhadap Anak
dan Kemenakan di Ranah Minang”, dalam Mimbar Hukum Volume 20 Nomor 2 (2008), 337.
3 Penjelasan lebih lanjut ditemukan dalam Siti Fatimah, “Kepemimpinan Tradisional Masyarakat Minangkabau pada Masa Pendudukan Jepang”, dalam Tingkap Volume VII Nomor 1 (2011), 75-88.
4 Syahda Guruh, Menimbang Otonomi Vs Federal: Mengembangkan Wacana
Federalisme dan Otonomi Luas Menuju Masyarakat Madani Indonesia (Bandung: Rosda Karya, 2000), 97.
DAMPAK PENERAPAN NILAI ADAT ... | 179
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Tingkat I Sumatera Barat menetapkan Surat Keputusan Nomor 259/GSB/1977 tentang penetapan jorong yang disamakan dengan desa. Efektivitas kebijakan ini terlihat dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Sebelum berlakunya regulasi pemerintahan desa ini, di Sumatera Barat terdapat 543 nagari.5 Untuk Sumatera Barat, eksistensi Undang-undang Pemerintahan Desa diperkuat dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1981. Keberadaan perda ini memecah jumlah nagari yang sudah ada sebelumnya menjadi 3.544 desa.6
Penetapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah jo. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diperkuat lagi dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari jo. Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari. Pemberlakuan Perda ini berimbas pada perubahan formasi dan jumlah pemerintahan terendah di Sumatera Barat. Sistem pemerintahan desa diganti dengan sistem pemerintahan nagari kembali.7 Jumlah nagari pada tahun 2006 adalah 519 nagari/desa/kelurahan.8 Pada tahun 2010, jumlah nagari menjadi 924 nagari/desa/kelurahan9 dan pada tahun 2011 menjadi 1.014 nagari/desa/kelurahan.10 Jumlah ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, mengingat adanya upaya pemekaran daerah. Secara statistik dapat digambarkan sebagai berikut.
5 Nuraini Budi Astuti, et. all., “Dilema Dalam Transformasi”, 154. 6 Jumlah ini terjabarkan dalam 3.138 desa dan 406 kelurahan. Bustanul Arifin,
et. all., Manajemen Suku, eds. Marwan & Bustanul Arifin (Jakarta: Solok Saiyo Sakato Press, 2012), 31.
7 Nagari dan desa tidak hanya berbeda dari segi ukuran luas dan urusan administrasinya saja, namun juga terkait dengan representasi padangan-padangan dunia serta falsafah-falsafah yang berlainan. Nagari merupakan mikrokosmos politis tata pemerintahan adat Minangkabau yang lebih luas, selaras dengan fundamen-fundamen dasar adat, matriklan dan bahasa. Sementara itu, desa merupakan unit terendah dalam sebuah negara birokratis. Mochtar Naim, “Nagari Versus Desa: Sebuah Kerancuan Struktural”, dalam Nagari, Desa dan Pembangunan Pedesaan di Sumatera Barat, eds. Mohammad Hasbi, et. all. (Padang: Yayasan Genta Budaya, 1990), 48.
8 Nuraini Budi Astuti, et. all., “Dilema Dalam Transformasi”, 154. 9 Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, Sumatera Barat Dalam Angka Tahun
2009/2010. 10 Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, Sumatera Barat Dalam Angka Tahun
2010/2011.
180 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Grafik 5.1. Perkembangan Jumlah Unit Pemerintahan Terendah di Sumatera Barat Berdasarkan Era Pemerintahan
Sumber : Diolah dari berbagai sumber.
Berdasarkan grafik 5.1. terlihat bahwa terjadi perubahan jumlah unit pemerintahan terendah setiap era pemerintahan. Banyaknya jumlah desa dengan ditetapkannya Undang-undang Pemerintahan Desa dikarenakan terjadinya diferensiasi pemerintahan pada tingkat terendah. Pada era sebelumnya, pemerintahan terendah yang didasarkan pada demokrasi adat adalah nagari yang terdiri dari beberapa jorong. Sedangkan pada era Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, unit pemerintahan terendah adalah desa. Desa merupakan nama bagi jorong yang berada di bawah nagari. Implikasi adanya diferensiasi pemerintahan pada tingkat terendah dapat diperhatikan dari tabel berikut.
543
3544
519
924 1014
Pra UU Nomor 5 Tahun 1979
Pasca UU Nomor 5 Tahun
1979
Era Otonomi Daerah (2006)
Era Otonomi Daerah (2010)
Era Otonomi Daerah (2011)
DAMPAK PENERAPAN NILAI ADAT ... | 181
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Tabel 5.1.
Perbandingan Jumlah Unit Pemerintahan di Sumatera Barat Era Pemerintahan Desa dan Nagari Tahun 1998 dan 2011
Unit Pemerintahan Era Pemerintahan Desa (1998)
Era Pemerintahan Nagari (2011)
Kabupaten 8 12 Kotamadya 6 7 Kecamatan 106 176
Desa 3.138 711 Kelurahan 406 303
Sumber : Diolah dari berbagai sumber. Merujuk pada tabel 5.1. terlihat bahwa pada tahun 1988, Provinsi
Sumatera Barat terdiri dari 8 kabupaten dan 6 kotamadya, sedangkan pada tahun 2011 terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kotamadya. Artinya, perubahan sistem pemerintahan desa ke pemerintahan nagari terjadi penambahan 4 kabupaten dan 1 kotamadya baru (peningkatan sebesar 35,41%). Demikian juga halnya dengan jumlah pemerintahan tingkat kecamatan yang mengalami penambahan dari jumlah awal sebanyak 106 kecamatan menjadi 176 kecamatan, terjadi penambahan 70 kecamatan baru (peningkatan sebesar 66,04%). Kondisi ini berbanding terbalik dengan jumlah desa dan kelurahan. Desa dan kelurahan selaku ujung tombak pemerintah melayani rakyat di tingkat paling bawah, mengalami pengurangan drastis. Jumlah desa yang awalnya 3.138 berubah menjadi 711 desa, terjadi penciutan sebanyak 2.427 desa (berkurang sebesar 77,34%). Kelurahan dengan jumlah awal 406 menciut menjadi 303 kelurahan, terjadi pengurangan sebanyak 103 kelurahan (berkurang sebesar 25,37%). Secara keseluruhan dari 3.544 desa dan kelurahan menciut menjadi 1.014 desa dan kelurahan, terjadi pengurangan sebanyak 2.530 desa dan kelurahan (berkurang sebanyak 71,39%).
Penambahan empat kabupaten dan satu kotamadya baru yang juga disertai dengan bertambahnya 70 kecamatan baru berbanding terbalik dengan semakin berkurangnya jumlah unit pemerintahan terendah. Idealnya, penambahan jumlah kabupaten atau kotamadya berbanding lurus dengan peningkatan jumlah kecamatan dan unit pemerintahan
182 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
terendah. Kondisi ini tidak berlaku di Sumatera Barat. Kebijakan otonomi daerah yang diikuti dengan proses kembali ke sistem pemerintahan nagari, tidak serta merta mengembalikan jumlah nagari sama seperti jumlah nagari sebelum ditetapkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979. Terjadi penciutan signifikan dari 3.544 desa menjadi 519 nagari/desa/kelurahan. Kondisi ini diakibatkan karena adanya Perda Nomor 13 Tahun 1983. Pada dasarnya, keberadaan Perda ini bertujuan untuk tetap melestarikan bentuk tradisional nagari terkait penyeragaman pemerintahan desa. Nagari dalam Perda ini dinyatakan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat yang terdiri dari himpunan beberapa suku, mempunyai wilayah tertentu dan memiliki harta kekayaan sendiri.11 Berdasarkan ketentuan tersebut, nagari tidak mempunyai hak dan wewenang dalam sistem pemerintahan. Nagari hanya mempunyai wewenang dalam mengatur kehidupan masyarakat nagari sepanjang adat. Kewenangan tersebut dipegang sepenuhnya oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). Nagari tidak lagi menjadi organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat karena kedudukannya sudah digantikan oleh desa.
Usaha untuk mempertahankan bentuk nagari dalam era pemerintahan desa tersebut ternyata mempengaruhi pemetaan wilayah nagari. Pada proses pembangunan nagari kembali, ada beberapa desa yang kemudian menjadi satu nagari. Terkait hal ini, Nuraini Budi Astuti12 telah menjabarkan 3 tipe dalam proses perubahan nagari menjadi desa, dan kemudian desa bertransformasi kembali menjadi nagari, sebagai berikut.
11 Pasal 1 huruf (e) Peraturan Daerah Sumatera Barat nomor 13 Tahun 1983
tentang Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. 12 Nuraini Budi Astuti, et. all., “Dilema Dalam Transformasi”, 154.
DAMPAK PENERAPAN NILAI ADAT ... | 183
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Bagan 5.1. Model Transformasi Bentuk Pemerintahan Terendah
di Sumatera Barat
Berdasarkan bagan 5.1. terlihat tiga tipikal transformasi bentuk
sistem pemerintahan terendah di Sumatera Barat. Pada tipe dua, unifikasi sistem pemerintahan terendah menjadi bentuk desa, terjadi pada tatanan jorong yang berada dalam nagari, sehingga satu nagari bisa membentuk beberapa desa. Pada era selanjutnya, desa-desa yang terbentuk dari satu nagari ini kemudian bergabung kembali karena berbagai faktor dan kemudian menjadi berubah menjadi satu desa kembali. Ketika kebijakan kembali ke sistem pemerintahan nagari, desa ini juga mengalami
DESA
DESA
NAGARI DESA DESA NAGARI
DESA
DESA
NAGARI DESA NAGARI
DESA
NAGARI
NAGARI
NAGARI
DESA
DESA
184 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
perubahan bentuk menjadi nagari. Transformasi pada tipe dua melalui fase yang tidak jauh berbeda dengan fase pada tipe pertama. Hanya saja, tipe dua tidak melalui tahapan penyatuan beberapa desa, namun langsung membentuk satu nagari baru. Transformasi yang terjadi sesuai dengan tipe satu dan dua ini tidaklah mempengaruhi jumlah nagari pasca kegagalan upaya unifikasi bentuk pemerintahan terendah. Transormasi tipe tiga merupakan bentuk yang paling mempengaruhi formasi dan jumlah pemerintahan terendah. Pada tipe ini, pemecahan nagari menjadi beberapa desa pada era unifikasi pemerintahan masih sama dengan dua tipe sebelumnya. Perbedaan muncul ketika proses transformasi bentuk desa ke bentuk nagari kembali. Ada beberapa desa yang kemudian bersatu dan menjadi nagari sendiri dan ada juga desa yang kemudian mandiri dan berdiri menjadi nagari sendiri. Proses ini terus berlangsung hingga saat ini. Sejak ditetapkannya ketentuan pemekaran wilayah dalam Perda Nagari, perkembangan jumlah nagari di Sumatera Barat semakin pesat. Pesatnya perkembangan ini dapat dirujuk dari data yang dirilis Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat dalam Buku Sumatera Barat Dalam Angka, sebagai berikut :
Tabel 5.2.
Perkembangan Unit Pemerintahan Di Sumatera Barat Tahun 2009 – 2011
Uraian 2009 2010 2011 Kabupaten 12 12 12
Kota 7 7 7 Kecamatan 176 176 176
Desa 126 126 125 Kelurahan 260 260 260
Nagari 627 628 648 Jorong 3.520 3.546 3.640
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2012. Merujuk pada tabel 5.2. di atas terlihat bahwa dalam rentang
waktu tahun 2009 hingga 2011, jumlah pemerintahan nagari dan juga jorong cenderung mengalami peningkatan, sementara itu jumlah kabupaten, kotamadya kecamatan dan kelurahan tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2011, jumlah desa berkurang satu dari tahun sebelumnya.persebaran jumlah unit pemerintahan di Sumatera Barat dapat diperhatikan dari tabel 5.3. berikut:
DAMPAK PENERAPAN NILAI ADAT ... | 185
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Tabel 5.3. Distribusi Unit Pemerintahan
Di Sumatera Barat Tahun 2011 Kabupaten
/Kota Luas Area
(km2) Jumlah
Kecamatan Nagari Kelurahan Desa Jorong Dusun Kab. Kep. Mentawai 6.011,35 10 - - 43 - 244 Kab. Pesisir Selatan 5.794,95 12 76 - - 365 -
Kab. Solok 3.738,00 14 74 - - 415 - Kab. Sijunjung 3.130,80 8 60 - 1 262 5
Kab. Tanah Datar 1.336,00 14 75 - - 396 - Kab. Padang Pariaman 1.328,79 17 60 - - 443 5
Kab. Agam 2.232,30 16 82 - - 467 - Kab. 50 Kota 3.354,30 13 79 - - 406 -
Kab. Pasaman 3.947,63 12 32 - - 209 - Kab. Solok Selatan 3.346,20 7 39 - - 208 - Kab. Dharmasraya 2.961,13 11 52 - - 261 -
Kab. Pasaman Barat 3.887,77 11 19 - - 208 - Kota Padang 694,96 11 - 104 - - - Kota Solok 57,64 2 - 13 - - -
Kota Sawahlunto 273,45 4 - 10 27 - 105 Kota Padang Panjang 23,00 2 - 16 - - -
Kota Bukit Tinggi 25,24 3 - 24 - - - Kota Payakumbuh 80,43 5 - 76 - - -
Kota Pariaman 73,36 4 - 17 54 - 170 Jumlah Total 42.279,30 176 648 260 125 3.640 525
Sumber: Diolah dari data BPS Sumatera Barat, 2012
186 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Pada dasarnya, pemekaran wilayah tidak hanya dipengaruhi oleh luasnya teritori suatu daerah. Menurut Suryadi,13 ada beberapa faktor pendorong terjadinya upaya pemekaran daerah, sebagai berikut. a. Nagari asal seringkali dianggap terlalu luas sehingga wali nagari dan
aparatnya mengalami kesulitan dalam mengelolanya. Pemekaran adalah salah satu alternatif untuk lebih memudahkan mengelola nagari. Sebagai efeknya, dengan pemekaran itu diharapkan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan nagari dapat dipacu;
b. Adanya ketentuan pemerintah yang menyatakan bahwa sebuah nagari berpenduduk minimal 2.500 jiwa. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak nagari asal berpenduduk lebih dari jumlah itu, sehingga muncul dorongan untuk memekarkan nagari asal;
c. Efek dari perubahan/peningkatan status beberapa kabupaten menjadi kota administratif atau kotamadya. Akibat perubahan ini, beberapa korong dari nagari-nagari tertentu yang berada di pinggir wilayah kota administratif atau kotamadya yang memperoleh peningkatan status tersebut, secara langsung atau tidak, ditarik untuk masuk ke dalam wilayah kota, sehingga mereka cenderung ingin memisahkan diri dari nagari induknya dan membentuk nagari atau kelurahan baru yang kemudian menjadi bagian dari kota administratif atau kodamadya bersangkutan ;
d. Adanya rencana pemerintah untuk mengucurkan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 1 milyar per tahun untuk dana pembangunan setiap nagari. Isu DAU ini mendominasi wacana akar rumput yang berkembang di lapau-lapau dari beberapa nagari yang akan dimekarkan. Namun isu ini tidak pernah terlaksana.
Ketentuan terkait pemekaran wilayah diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Regulasi ini kemudian dipertegas dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan. Berdasarkan pada kedua regulasi ini,14 untuk membentuk desa baru di wilayah Sumatera
13 Suryadi, “Tentang Pemekaran Nagari”, dalam Haluan (Padang, 9 Januari
2012). Suryadi adalah seorang dosen dan peneliti Leiden University Institute for Area Studies, Leiden, Belanda. Keterangan lebih lanjut bisa ditemukan dalam http://niadilova.blogdetik.com/index.php/archives/871 akses tanggal 22 Mei 2013, 20.27 WIB.
14 Penjelasan pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Hal yang sama juga dinyatakan dalam pasal 3 huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006.
DAMPAK PENERAPAN NILAI ADAT ... | 187
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
diharuskan mempunyai minimal 1.000 jiwa atau 200 Kepala Keluarga. Sementara itu, jika dirujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2006 dan pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, dinyatakan bahwa untuk membentuk kelurahan baru di wilayah Sumatera diharuskan mempunyai 2000 jiwa atau 400 Kepala Keluarga. Terkait dengan masalah luas wilayah, merujuk pada pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 menyatakan bahwa untuk wilayah Sumatera diharuskan mempunyai wilayah minimal 5 km2.
Jika dirujuk pada statistik jumlah penduduk dan hubungannya dengan luas wilayah di Sumatera Barat, pada dasarnya dapat dilakukan pemekaran dengan jumlah yang sangat signifikan. Pakar tata Negara, seperti Marlis Muhammad telah memberikan beberapa rekomendasi sebagai alternatif dalam upaya pemerataan pemekaran wilayah di Sumatera Barat. Sebagai ilustrasi, dapat diperhatikan dari data berikut.
Grafik 5.2.
Kepadatan Penduduk di Sumatera Barat Tahun 2011 (dalam jiwa/km2)
Sumber: Sumatera Barat Dalam Angka, 2012.
12.87
74.83
94.16
65.39
255.16
296.62
205.84
105.06
64.91
43.76
65.89
95.43
1214.91
1046.17
210.25
2070.39
4437.53
1472.52
1090.4
Kab. Kep. Mentawai
Kab. Pesisir Selatan
Kab. Solok
Kab. Sijunjung
Kab. Tanah Datar
Kab. Padang Pariaman
Kab. Agam
Kab. 50 Kota
Kab. Pasaman
Kab. Solok Selatan
Kab. Dharmasraya
Kab. Pasaman Barat
Kota Padang
Kota Solok
Kota Sawahlunto
Kota Padang Panjang
Kota Bukittinggi
Kota Payakumbuh
Kota Pariaman
188 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Berdasarkan grafik 5.2. di atas terlihat bahwa rata-rata daerah kotamadya yang relatif lebih kecil dibanding daerah kabupaten mempunyai kepadatan penduduk yang lebih tinggi daripada kabupaten. Ketidakseimbangan jumlah penduduk dan luas wilayah berimbas pada kesenjangan yang sangat signifikan terhadap kepadatan penduduk. Kotamadya Bukittinggi merupakan daerah dengan penduduk terpadat sebanyak 4.473,53 jiwa/km2 dan Kabupaten Mentawai dengan kepadatan penduduk terendah, sebanyak 12,87 jiwa/km2. Ketidakseimbangan juga ditemukan dari persebaran jumlah nagari pada masing-masing kecamatan, sebagai berikut :
Tabel 5.4.
Distribusi Jumlah Nagari per Kecamatan Di Sumatera Barat Tahun 2011
Jumlah Nagari
Dalam Satu Kecamatan Jumlah
Kecamatan 1 Nagari 9 Kecamatan 2 Nagari 19 Kecamatan 3 Nagari 20 Kecamatan 4 Nagari 26 Kecamatan 5 Nagari 20 Kecamatan 6 Nagari 14 Kecamatan 7 Nagari 11 Kecamatan 8 Nagari 7 Kecamatan 9 Nagari 5 Kecamatan
10 Nagari 2 Kecamatan 11 Nagari 1 Kecamatan 12 Nagari 2 Kecamatan
Sumber : Diolah dari Murlis Muhammad, 2012. Merujuk pada tabel 5.4. terlihat bahwa ada 26 kecamatan yang
masing-masingnya terdiri dari 4 nagari. Terdapat 2 kecamatan masing-masing terdiri dari 12 nagari. Ketidakseimbangan penyebaran jumlah nagari di setiap kecamatan menarik untuk disimak lebih lanjut. Pemerintah telah menetapkan ketentuan-ketentuan terkait dengan pembentukan kecamatan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1), dinyatakan bahwa untuk wilayah kabupaten setiap kecamatan minimalnya harus terdiri dari 10 desa atau nagari di Sumatera Barat dan untuk wilayah
DAMPAK PENERAPAN NILAI ADAT ... | 189
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
kotamadya minimal harus terdiri dari 5 desa atau nagari. Adanya konversi nagari menjadi desa dan kemudian kembali di-nagari-kan berakibat pada berkurangnya jumlah pemerintahan daerah terendah di Sumatera Barat.
Fenomena pemekaran wilayah merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dielakkan lagi di Sumatera Barat. Pada satu pihak, upaya ini terkait dengan isu nasional dan di pihak lain terkait dengan isu daerah. Dalam perspektif nasional, wacana pemekaran wilayah, berhubungan dengan berbagai kepentingan seperti politik, ekonomi dan sosial yang tersembunyi di baliknya. Hal ini mengikut tren politik yang terjadi di Indonesia pasca tumbangnya Orde Baru. Proses pemekaran wilayah nagari di Sumatera Barat sampai saat ini masih berlangsung. Berdasarkan tabel distribusi teoritis di atas, jika dirujuk pada regulasi yang ada pada dasarnya dapat dilakukan banyak pemekaran wilayah di Sumatera Barat. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti dapat diimplementasikan dengan mudah. Ada begitu banyak pertimbangan lain yang mempunyai peran penting demi terwujudnya daerah berdasarkan regulasi yang sudah ditetapkan. Salah satu faktor penting yang harus dipertimbangkan adalah substansi dalam pemerintahan nagari itu sendiri.
Terkait dengan pelayanan publik, pengukuran kinerja dilandasi pemahaman bahwa peningkatan pelayanan adalah upaya perbaikan hubungan antara masyarakat dan negara. Hal ini berkaitan dengan perbaikan kualitas hidup dan pemenuhan hak-hak pengguna layanan sebagai warga negara berhadapan dengan negara. Dari serangkaian indikator yang tersedia, dipilih sejumlah indikator minimal yang terkait langsung dengan sarana masyarakat untuk mempertahankan dan mengembangkan daya hidupnya. Otonomi daerah memberikan peluang untuk terpenuhinya kebutuhan pelayanan minimal tesebut di daerah dengan harapan akan menjadi sarana dan kondisi utama bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Kewenangan yang dimiliki daerah untuk menyelenggarakan pelayanan umum sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi daerah akan mendekatkan pelayanan tersebut pada masyarakat. Dengan demikian diharapkan aspirasi masyarakat lebih terakomodir sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan umum yang tidak sekedar minimal, melainkan pelayanan yang optimal.
Sebagai gambaran umum, kondisi keuangan di Provinsi Sumatera Barat dapat diperhatikan dari perkembangan realisasi pendapatan dan belanja daerah sejak mulai ditetapkannya regulasi mengenai sistem pemerintahan nagari. Perkembangan tersebut dapat diperhatikan dalam grafik 5.3. berikut.
190 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Grafik 5.3. Perkembangan Realisasi Pendapatan dan Belanja
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 – 2012
Sumber: Diolah dari data Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Sumatera Barat, 2013.15
15 Data realisasi pendapatan dan belanja tahun 2007 didasarkan pada Perda
Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2007, data realisasi pendapatan dan belanja tahun 2008 didasarkan pada Perda Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2008, data realisasi pendapatan dan belanja tahun 2008 didasarkan pada Perda Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2008, data realisasi pendapatan dan belanja tahun 2009 didasarkan pada Perda Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2009, data realisasi pendapatan dan belanja tahun 2010 didasarkan pada Perda Sumatera
Rp1,281,399,815,356.90
Rp1,727,123,663,925.10
Rp2,026,241,165,035.01Rp1,920,971,382,916.73
Rp2,183,958,892,494.08
Rp2,922,582,139,905.33
Rp1,245,441,502,848.78
Rp1,641,356,587,192.43Rp1,657,403,919,450.58
Rp2,239,753,491,320.88Rp2,132,956,528,415.00
Rp2,922,582,139,905.33
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Pendapatan
Belanja
DAMPAK PENERAPAN NILAI ADAT ... | 191
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Berdasarkan grafik 5.3. di atas, terlihat bahwa secara umum, pendapatan Provinsi Sumatera Barat cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar Rp. 105.269.782.118,28,- atau sekitar ± 5,20% dari tahun sebelumnya. Sementara itu belanja daerah cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali tahun 2011 mengalami penurunan ± 4,77% atau sebesar Rp. 106.796.967.905,88,-. Peningkatan pendapatan daerah tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar ± 34,81% dan pada tahun 2012 sebesar ± 33,82%. Sementara itu, peningkatan belanja daerah tertinggi adalah pada tahun 2012 sebesar ± 37,02%. Pengaruh kecenderungan peningkatan realisasi pendapatan dan belanja daerah ini dapat dijabarkan dalam beberapa aspek.
1. Bidang Pendidikan
Bidang pendidikan merupakan salah satu urusan wajib dalam pemerintahan. Perkembangan realisasi belanja dalam bidang pendidikan dapat diperhatikan dalam grafik 5.4. berikut :
Grafik 5.4.
Perkembangan Realisasi Belanja Bidang Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 – 2012
Sumber: Diolah dari data Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Sumatera Barat, 2013.
Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2010, data realisasi pendapatan dan belanja tahun 2011 didasarkan pada Perda Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011 dan data realisasi pendapatan dan belanja tahun 2012 didasarkan pada database Bidang Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Sumatera Barat, mengingat laporan pertanggungjawaban ini belum selesai disidangkan di DPRD.
Rp68,532,514,533.00
Rp120,542,485,341.00
Rp139,104,127,801.00
Rp161,818,999,107.00
Rp110,404,209,289.00Rp98,197,111,328.00
2007 2008 2009 2010 2011 2012
192 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Berdasarkan grafik 5.4. terlihat bahwa realisasi belanja bidang pendidikan mengalami peningkatan hingga tahun 2010 dan mengalami penurunan pada tahun 2011 dan 2012. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar Rp. 52.009.970.808,00,- atau ± 75,89%. Penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar Rp. 51.414.789.818,00,- atau ± 31,77%. Jika dihubungkan dengan realisasi belanja daerah secara umum, maka perkembangan persentase realisasi belanja bidang pendidikan dapat diperhatikan dalam grafik 5.5. berikut:
Grafik 5.5.
Perkembangan Persentase Realisasi Belanja Bidang Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 – 2012
Sumber: Diolah dari data Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Sumatera Barat, 2013.
Berdasarkan grafik 5.5. di atas, terlihat bahwa perkembangan
presentase realisasi belanja bidang pendidikan mengalami peningkatan hingga tahun 2009 sebesar 8.39% dan mengalami penurunan sejak tahun 2010 sampai 2012. Persentase terendah terjadi pada tahun 2012 sebesar 3.36%. Persentase realisasi ini berada di bawah batas minimum alokasi bidang pendidikan yang sudah ditetapkan berdasarkan undang-undang sebesar 20%. Minimnya realisasi alokasi belanja pada bidang pendidikan dikarenakan adanya pemisahan Dinas Pendidikan dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga di Sumatera Barat. Indikator yang dipergunakan penilaian
5.50%
7.34%
8.39%
7.22%
5.18%
3.36%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
DAMPAK PENERAPAN NILAI ADAT ... | 193
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
terhadap pencapaian dalam bidang pendidikan, adalah rasio jumlah murid per sekolah, rasio jumlah guru per sekolah dan rasio jumlah murid per jumlah guru dan angka partisipasi sekolah.
Tabel 5.5.
Jumlah Sekolah Di Sumatera Barat Tahun 2007 – 2011
URAIAN 2007 2008 2009 2010 2011 TK 1.714 1.712 1.804 1.918 1.967 SD 4.017 4.032 3.815 4.180 4.125 MI 114 115 117 119 119
SMP 560 568 618 676 747 MTs 360 359 366 369 372 SMU 244 244 253 222 259 SMK 165 146 165 177 180 MA 169 169 169 183 183
TOTAL 7.343 7.345 7.307 7.844 7.952 Sumber: Diolah dari data Sumatera Barat Dalam Angka, 2012.
Berdasarkan tabel 5.5. terlihat bahwa sekolah di Sumatera
Barat cenderung mengalami peningkatan jumlah setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2009, jumlah Taman Kanak-kanak (TK), MI, SMP, MTs, SMK dan MA cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berbeda dengan jumlah SD dan SMP yang secara bersamaan mengalami penurunan jumlah pada tahun 2009 dan SMU pada tahun 2010.
Tabel 5.6. Jumlah Murid Di Sumatera Barat
Tahun 2007 – 2011 URAIAN 2007 2008 2009 2010 2011
TK 61.070 68.836 70.378 68.576 68.576 SD 660.157 659.136 629.066 680.491 678.504 MI 14.602 13.775 16.566 16.568 17.537
SMP 185.972 198.557 236.502 201.138 206.957 MTs 62.321 63.141 64.320 69.944 71.477 SMU 107.650 115.165 128.611 104.792 130.011 SMK 46.962 52.720 55.085 59.307 65.570 MA 23.569 24.297 23.418 25.205 25.574
TOTAL 1.162.303 1.195.627 1.223.946 1.220.021 1.264.206 Sumber: Diolah dari data Sumatera Barat Dalam Angka, 2012.
194 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Berdasarkan tabel 5.6. terlihat bahwa pada dasarnya jumlah murid sekolah di Sumatera Barat cenderung mengalami peningkatan, terkecuali pada tahun 2010 pada tingkat SMP yang mengalami penurunan sebesar 0,15%. Penurunan ini disebabkan adanya bencana alam gempa bumi yang terjadi di Sumatera Barat pada 30 September 2009. Meskipun jumlah siswa SMP mengalami penurunan pada tahun 2010, jumlah siswa MTs mengalami peningkatan yang signifikan dibanding tren peningkatan di tahun-tahun sebelumnya, yakni sebesar 0,09%.
Tabel 5.7.
Jumlah Guru Di Sumatera Barat Tahun 2007 – 2011
URAIAN 2007 2008 2009 2010 2011
TK 5.239 6.832 5.849 6.054 6.054 SD 40.871 44.572 48.430 44.956 44.956 MI 1.191 1.191 1.532 1.648 1.698
SMP 16.626 16.768 22.242 18.372 19.484 MTs 7.424 5.648 7.997 8.067 8.330 SMU 10.307 10.530 12.871 10.480 11.321 SMK 6.494 6.171 6.425 6.885 7.030 MA 3.683 2.706 1.743 4.075 5.947
TOTAL 91.835 94.418 107.089 100.537 104.811 Sumber: Diolah dari data Sumatera Barat Dalam Angka, 2012.
Berdasarkan tabel 5.7. terlihat bahwa jumlah guru di Sumatera Barat cenderung mengalami peningkatan secara bertahap, kecuali pada tahun 2010 yang mengalami pengurangan senilai 6,12%. Hal ini merupakan salah satu dampak terjadinya bencana alam gempa bumi di Sumatera Barat. Penurunan ini terjadi pada tingkat SD, SMP dan SMU, sementara pada jenjang pendidikan lainnya tetap mengalami peningkatan.
Pengukuran rasio murid per sekolah, guru per sekolah dan murid per guru didasarkan pada program wajib belajar 12 tahun, sehingga variabel yang dipergunakan adalah tingkat satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMU/SMK/MA. Pengukuran rasio ini akan memperlihatkan perkembangan perbandingan antara guru, sekolah dan murid yang terjadi di Sumatera Barat pada tahun 2007 hingga tahun 2011, sebagai berikut:
DAMPAK PENERAPAN NILAI ADAT ... | 195
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Grafik 5.6. Perkembangan Rasio Murid per Sekolah
Di Sumatera Barat Tahun 2007 - 2011
Sumber: Diolah dari data Sumatera Barat Dalam Angka, 2012.
Berdasarkan grafik 5.6. terlihat bahwa angka rasio murid per sekolah tertinggi terjadi pada tahun 2009 sebesar 209,63 siswa per sekolah dan terendah pada tahun 2010 sebesar 194,31 murid per sekolah. Tren rasio murid per sekolah di Sumatera Barat cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2010. Pada tahun 2007 terjadi peningkatan senilai 2,25% dan pada tahun 2009 terjadi peningkatan senilai 4,80%. Sementara pada tahun 2010 terjadi penurunan sebesar 7,31%. Pada tahun 2011 kembali terjadi peningkatan sebesar 2,81%. Penurunan yang signifikan pada tahun 2010 diakibatkan karena adanya bencana alam gempa bumi yang terjadi di Sumatera Barat pada 30 September 2009. Setelah tahun 2010, peningkatan kembali terjadi dengan persentase yang tidak jauh berbeda dengan persentase sebelum tahun 2010.
195.64
200.04
209.63
194.31
199.77
2007 2008 2009 2010 2011
196 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Grafik 5.7. Perkembangan Rasio Guru per Sekolah di Sumatera Barat Tahun 2007 - 2011
Sumber: Diolah dari data Sumatera Barat Dalam Angka, 2012.
Berdasarkan grafik 5.7. terlihat bahwa tren rasio guru per
sekolah di Sumatera Barat cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2010. Angka rasio guru per sekolah tertinggi terjadi pada tahun 2009 sebanyak 18,4 guru per sekolah dan terendah pada tahun 2007 sebesar 15,83 guru per sekolah. Pada tahun 2008, peningkatan rasio guru per sekolah meningkat sebesar 1,11% dan pada tahun 2009 meningkat lagi sebesar 18,33%. Sementara itu, pada tahun 2010 terjadi penurunan rasio guru per sekolah sebesar 13,37%. Rasio guru per sekolah kembali mengalami peningkatan pada tahun 2011 sebesar 3,51%.
15.3815.55
18.4
15.94
16.5
2007 2008 2009 2010 2011
DAMPAK PENERAPAN NILAI ADAT ... | 197
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Grafik 5.8. Perkembangan Rasio Murid per Guru di Sumatera Barat Tahun 2007 - 2011
Sumber: Diolah dari data Sumatera Barat Dalam Angka, 2012.
Pada grafik 5.8. terlihat bahwa tren rasio murid per guru relatif
stabil setiap tahunnya. Angka rasio murid per guru tertinggi terjadi pada tahun 2008 senilai 12,87 murid per guru dan terendah pada tahun 2009 senilai 11,35 murid per guru. Pada tahun 2008, peningkatan rasio murid per guru meningkat sebesar 1,18% dan pada tahun 2009 berhasil ditekan menjadi 11,81%. Pada tahun 2010, rasio murid per guru kembali mengalami peningkatan sebesar 7,4% dan pada tahun 2011 kembali berhasil ditekan sebesar 0,66%.
Secara umum terlihat bahwa kualitas pelayanan pemerintah dalam bidang pendidikan relatif stabil. Pada tahun 2009, kualitas pelayanan pemerintah dalam bidang pendidikan berada pada posisi paling baik dan kemudian mengalami penurunan pada tahun berikutnya. Penurunan ini dipengaruhi oleh bencana alam gempa bumi yang terjadi di daerah Sumatera Barat pada tanggal 30 September 2009. Kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana alam tersebut sangat mempengaruhi perkembangan jumlah sekolah, murid dan tenaga guru. Kondisi berpengaruh pada tingkat rasio masing-masing indikator seperti yang dijelaskan dalam grafik di atas. Meskipun demikian, peningkatan yang terjadi pada 2 tahun selanjutnya menunjukkan kecenderungan peningkatan secara bertahap.
Faktor lain yang juga harus diperhatikan adalah siswa yang terlibat dalam pendidikan. Partisipasi siswa menjadi salah satu faktor penting untuk menilai ketepatan sasaran upaya pemerintah dalam
12.72 12.87
11.35
12.19 12.11
2007 2008 2009 2010 2011
198 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
memberikan pelayanan bidang pendidikan. Klasifikasi tersebut dapat diperhatikan dari grafik berikut :
Grafik. 5.9.
Perkembangan Presentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas Menurut Partisipasi Sekolah di Sumatera Barat
Tahun 2007 - 2011
Sumber: Diolah dari data Sumatera Barat Dalam Angka, 2012.
5.96% 6.10% 5.00% 5.29% 5.90%
28.76% 28.44% 28.20% 29.19% 28.61%
65.55% 65.46% 66.90% 65.52% 65.50%
2007 2008 2009 2010 2011Tidak Bersekolah Lagi Masih Sekolah
Tidak/Belum Pernah Sekolah
DAMPAK PENERAPAN NILAI ADAT ... | 199
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Berdasarkan grafik 5.9. terlihat bahwa tren persentase partisipasi anggota masyakarat dalam pendidikan relatif stabil pada kisaran angka 28,2% hingga 29,19%. Persentase tersebut dijabarkan dalam angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni dan angka partisipasi sekolah Provinsi Sumatera Barat. Angka partisipasi dalam suatu kegiatan penting untuk diketahui, karena dengan mengetahui angka partisipasi tersebut dapat dinilai apakah kegiatan tersebut disukai masyarakat atau tidak disukai. Semakin besar angka partisipasi suatu program pendidikan berarti program, lembaga, daerah tersebut berkualitas, sebaliknya kurang dan peserta banyak berhenti dalam proses pelaksanaan program berarti program, lembaga dan daerah tersebut tidak berkualitas.
Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan, berapapun usianya, terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Nilai APK bisa lebih dari 100%. Hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia diatas 12 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SD atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD. Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda.
APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing
200 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
jenjang pendidikan. Perkembangan APK Provinsi Sumatera Barat dijelaskan dalam grafik 5.10. berikut.
Grafik 5.10. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2003 – 2012
Sumber: Diolah dari data Sumatera Barat dalam Angka, 2012.
Merujuk pada grafik 5.10. terlihat bahwa terjadi fluktuasi sederhana angka partisipasi kasar secara bervariasi pada masing-masing satuan pendidikan. Pada satuan pendidikan SD/MI, angka partisipasi kasar tertinggi pada tahun 2007 senilai 112,05% dan terendah pada tahun 2011 senilai 104,08%. Pada satuan pendidikan SMP/MTs, angka partisipasi kasar tertinggi pada tahun 2005 senilai 89,03% dan terendah pada tahun 2010 senilai 80,34%. Pada satuan pendidikan SMA/MA, angka partisipasi kasar tertinggi pada tahun 2009 senilai 74,37% dan terendah pada tahun 2003 senilai 63,92%.
Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah
105.23%106.66%105.60%108.85%
112.05%110.87%110.31%110.63%104.08%106.73%
87.86% 88.80% 89.03%83.53% 84.87% 85.37%
81.13% 80.34%
87.49% 88.00%
63.92% 65.32%68.70% 67.69% 70.47% 71.04%
74.37% 72.82%69.18%
72.66%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012SD/MI SMP/MTs SMU/MA
DAMPAK PENERAPAN NILAI ADAT ... | 201
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.
Jika seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya under estimate karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu. Misalnya, Seorang anak usia 6 tahun bersekolah di SD kelas 1 tidak akan masuk dalam penghitungan APM karena usianya lebih rendah dibanding kelompok usia standar SD yaitu 7-12 tahun. Perkembangan APM Provinsi Sumatera Barat dapat diperhatikan dari grafik 5.11. berikut :
Grafik 5.11. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2003 – 2012
Sumber: Diolah dari data Sumatera Barat Dalam Angka, 2012.
92.59%93.64%93.65%94.17%94.45%94.66%94.75%95.51%93.47%95.68%
66.00%69.55%68.77%67.77%67.33%67.63%67.61%68.22%67.10%
70.18%
49.88%53.13%53.36%51.05%
54.23%54.68%54.50%55.06%54.05%55.84%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012SD/MI SMP/MTs SMU/MA
202 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Berdasarkan grafik 5.11. terlihat bahwa terjadi peningkatan APM secara bervariasi pada masing-masing satuan pendidikan. Pada satuan pendidikan SD/MI, APM tertinggi pada tahun 2012 senilai 95,68% dan terendah pada tahun 2003 senilai 92,59%. Pada satuan pendidikan SMP/MTs, APM tertinggi pada tahun 2012 senilai 70,18% dan terendah pada tahun 2003 senilai 66%. Pada satuan pendidikan SMA/MA, APM tertinggi pada tahun 2012 senilai 55,84% dan terendah pada tahun 2003 senilai 49,88%.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan menjadi indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Perkembangan APS Provinsi Sumatera Barat terlihat dalam grafik 5.12. berikut.
Grafik 5.12. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2003 – 2012
Sumber: Diolah dari data Sumatera Barat Dalam Angka, 2012.
86.70%88.73%89.24%88.45%88.52%88.70%88.79%89.51%89.64%90.66%
63.23%66.41%67.12%64.29%65.35%65.73%65.25%65.65%68.12%
71.56%
20.77%22.33%21.40%18.29%20.88%21.22%20.58%21.26%22.00%
27.80%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 201213-15 Tahun 16-18 Tahun 19-24 Tahun
DAMPAK PENERAPAN NILAI ADAT ... | 203
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Berdasarkan grafik 5.12. terlihat bahwa tingkat partisipasi sekolah di Sumatera Barat secara umum mengalami peningkatan. Pada kelompok usia 13-15 tahun, APS tertinggi pada tahun 2012 senilai 90,66% dan terendah pada tahun 2003 senilai 86,7%. Pada kelompok usia 16-18 tahun, APS tertinggi pada tahun 2012 senilai 71,56% dan terendah pada tahun 2003 senilai 63,23%. Pada kelompok usia 19-24 tahun, APS tertinggi pada tahun 2012 senilai 27,8% dan terendah pada tahun 2006 senilai 18,29%. Peningkatan APS terjadi secara berkesinambungan meskipun pada beberapa kelompok usia terjadi penurunan, namun pada tahun berikutnya mengalami peningkatan kembali. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan kualitas pelayanan dalam bidang pendidikan di Sumatera Barat.
2. Bidang Kesehatan
Bidang kesehatan merupakan bagian dari urusan wajib dalam APBD Sumatera Barat. Perkembangan realisasi belanja bidang pendidikan di Sumatera Barat dapat diperhatikan dalam grafik 5.13. berikut.
Grafik 5.13. Perkembangan Realisasi Belanja Bidang Kesehatan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 – 2012
Sumber: Diolah dari data Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Sumatera Barat, 2013.
Rp129,040,506,195.23
Rp157,953,083,948.90
Rp187,228,196,391.33
Rp210,932,018,215.00Rp229,811,439,899.00
Rp305,340,796,006.75
2007 2008 2009 2010 2011 2012
204 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Berdasarkan grafik 5.13. terlihat bahwa tren perkembangan realisasi belanja bidang kesehatan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan realisasi belanja bidang kesehatan tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar Rp. 2.132.956.523.415,00,- atau 10,77% dan peningkatan terendah terjadi pada tahun 2010 sebesar Rp. 2.239.753.491.320,88,- atau 9,42%. Jika dibandingkan dengan besarnya realisasi belanja Provinsi Sumatera Barat, makan perkembangan persentase belanja bidang kesehatan dapat digambarkan dalam grafik 5.14. berikut :
Grafik 5.14.
Perkembangan Persentase Realisasi Belanja Bidang Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 – 2012
Sumber: Diolah dari data Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Sumatera Barat, 2013.
Berdasarkan grafik 5.14. di atas, terlihat bahwa tren
perkembangan presentase realisasi belanja bidang kesehatan mengalami fluktuasi sederhana. Persentase tertinggi terjadi pada tahun 2009 sebesar 11,30% dan terendah pada tahun 2010 sebesar 9,42%.
Salah satu tolok ukur indikator pelayanan publik dalam bidang kesehatan adalah angka kematian bayi. Pelayanan publik dalam bidang kesehatan terjabarkan dalam pelayanan terhadap penanganan proses persalinan yang dilakukan pada instansi medis yang disediakan pemerintah. Sebagai gambaran umum, proporsi kelahiran berdasarkan penolongnya di Sumatera Barat terlihat dalam grafik 5.15. berikut :
10.36%
9.62%
11.30%
9.42%
10.77%
10.45%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
DAMPAK PENERAPAN NILAI ADAT ... | 205
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Grafik 5.15. Proporsi Kelahiran Berdasarkan Penolongnya
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011
Sumber: Indikator Kesehatan Sumatera Barat, 2011.
Merujuk pada grafik 5.15. terlihat bahwa 92% proses
kelahiran dilakukan oleh instansi medis yang disediakan oleh pemerintahan. Kondisi ini menunjukkan semakin baiknya pelayanan pemerintah dalam menyediakan sarana dan tenaga medis yang menjadi penolong kelahiran. Hal ini berpengaruh terhadap perkembangan angka kematian bayi, sebagai berikut.
Bidan, 71.00%
Dokter, 20.00%
Famili, 1.00%Dukun, 7.00%
Tenaga Medis Lainnya, 1.00
%
206 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Grafik 5.16. Perkembangan Angka Kematian Bayi
Provinsi Sumatera Barat Tahun 1971 – 2010 (dalam per 1000 kelahiran)
Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik Nasional, 2012.
Berdasarkan grafik 5.16. terlihat bahwa sejak tahun 2000, angka kematian bayi berhasil diturunkan secara bertahap. Dalam rentang tahun 2002 hingga tahun 2010, angka kematian bayi berhasil ditekan hingga 43,66% dari 52,66 kematian per seribu kelahiran menjadi 29,67 kematian per seribu kelahiran. Tren penurunan angka kematian bayi sudah terjadi sejak tahun 1971, sehingga tren yang terjadi setelah tahun 2000 boleh jadi hanya merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya. Keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menurunkan angka kematian bayi mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan dalam bidang kesehatan mengalami peningkatan setiap tahunnya.
3. Bidang Infrastruktur Perhubungan Dasar
Pelayanan dalam bidang infrastruktur perhubungan dasar didasarkan kepada ketersediaan jalan, baik jalan nasional ataupun jalan provinsi dengan memperhatikan kondisinya, sebagai berikut:
152
121
7467.6 65.8
52.6648 47
29.67
1971 1980 1990 1994 1997 2000 2002 2007 2010
DAMPAK PENERAPAN NILAI ADAT ... | 207
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Grafik 5.17. Perkembangan Panjang dan Kondisi Jalan
di Sumatera Barat Tahun 2007 – 2011 (dalam kilometer)
Sumber: Diolah dari data Sumatera Barat Dalam Angka, 2012.
Merujuk pada grafik 5.17. terlihat bahwa antara tahun 2007
hingga tahun 2009 terjadi penurunan kualitas jalan, baik kategori jalan nasional ataupun jalan provinsi. Pada tahun 2011, 39,2% kondisi jalan nasional mengalami peningkatan kualitas. Sementara itu, dalam rentang tahun 2007 hingga 2011 kualitas jalan provinsi telah
1033.6 1033.6
762.48
619.47
1094.93
166.48 166.48
450.41
593.42
117.97
1042.641021.54
1002.19966.26
990.87
111.3132.4
151.75 157.68 163.06
2007 2008 2009 2010 2011Jalan Nasional (Steady) Jalan Nasional (No Steady)
Jalan Provinsi (Steady) Jalan Provinsi (No Steady)
208 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
mengalami penurunan kualitas sebesar 4,49%. Kondisi ini diakibatkan fokus pembangunan pada masa ini adalah pembangunan bidang pendidikan dan ekonomi. Faktor lain yang juga berkontribusi terhadap kondisi adalah terjadinya bencana alam gempa bumi di Sumatera Barat pada 30 September 2009.
Terlepas dari keadaan jalan nasional dan jalan propinsi, implementasi sistem pemerintahan nagari juga meningkatkan semangat gotong royong masyarakat dalam pembukaan ruas jalan baru dan perbaikan kondisi jalan. Fenomena pemekaran wilayah nagari menunut adanya pembukaan beberapa ruas jalan baru guna menunjang akses transportasi antar nagari. Berdasarkan keterangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan,16 pertumbuhan panjang jalan didorong oleh swadaya masyarakat dan juga dari dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP). Masyarakat di nagari atau kampung bergotong royong membangun jalan baru. Sebagian jalan tersebut dibuat untuk menghubungkan perkampungan dan sebagian lain menjadi akses menuju perkebunan.
Grafik 5.18.
Perkembangan Ruas Jalan Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2008 – 2011
(dalam kilometer)
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pesisir Selatan, 2012.
Berdasarkan grafik 5.18. terlihat bahwa panjang ruas jalan di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami peningkatan signifikan sejak tiga tahun terakhir yakni sekitar 780 kilometer hingga akhir 2011. Pertumbuhan panjang jalan di kabupaten itu disebabkan banyaknya
16 Harian Pos Metro Padang, 22 November 2012.
1346
2126
2008 2011
DAMPAK PENERAPAN NILAI ADAT ... | 209
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
program-program pemberdayaan yang berbasis partisipasi dan swadaya masyarakat. Swadaya masyarakat disalurkan melalui berbagai program pemberdayaan seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Pogram pemberdayaan oleh pemerintah pusat dimulai sejak tahun 2007. Sebagian besar pemerintah mengarahkan untuk pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, disamping program pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Penambahan panjang jalan kabupaten hingga 780 kilometer dalam rentang tahun 2008 sampai 2011 sebagian besarnya terjadi pada ruas jalan perekonomian masyarakat yakni jalan usaha tani, perkebunan, nelayan dan sebagainya.
Tidak hanya di Kabupaten Pesisir Selatan, pembukaan jalan baru dengan inisiatif masyarakat juga terjadi di hampir seluruh daerah Sumatera Barat. Menurut Walinagari Labuh Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, masyarakat Jorong Labuh membangun jalan usaha tani sepanjang 1.500 meter dengan lebar dua meter secara untuk memperlancar petani dalam menjalankan aktivitas pertanian. Pembukaan jalan pertanian tersebut menghubungkan puluhan hektare sawah petani, sehingga memudahkan proses pengangkutan bibit, pupuk, dan produksi hasil pertanian lainnya. Pembangunan jalan usaha tani itu didukung oleh seluruh elemen masyarakat yang ada di nagari. Peran swadaya masyarakat dalam pembukaan jalan baru ini cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan adanya wakaf tanah oleh pemiliknya untuk kepentingan pembebasan lahan dan proses pengerjaan jalan melalui sistem manunggal.
Merujuk kepada laporan Tim Monitoring Pemko Padang yang diketuai Sekda diwakili Asisten III Corry Saidan, terlihat bahwa swadaya masyarakat yang diakomodasikan melalui Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) mempunyai pengaruh penting dalam pembangunan jalan baru. Pembangunan jalan baru tersebut dilaksanakan secara gotong royong oleh anggota masyarakat. Masyarakat RT 02 RW 03 Kelurahan Gurun Laweh Kecamatan Nanggalo membangun jalan sepanjang 340 meter dengan lebar badan jalan 3,5 meter dan masyarakat RT 02 RW 2 Kelurahan Kampung Lapai membangun jalan sepanjang 34 meter dengan lebar badan jalan 6 meter.
Berdasarkan beberapa upaya pembukaan jalan baru atas inisiatif masyarakat terlihat bahwa semangat bergotong royong mempunyai peran penting dalam masyarakat. Pemberlakuan kembali sistem pemerintahan nagari terbukti mampu merevitalisasi nilai-nilai abstrak dalam bentuk semangat kebersamaan dalam nagari. Hal ini
210 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
terbukti dengan banyaknya upaya masyarakat yang secara sukarela memberikan lahannya untuk pembukaan ruas jalan baru dan bergotong royong dalam proses pengerjaannya.
4. Bidang Daya Saing Daerah
Merujuk pada beberapa teori, disimpulkan bahwa daya saing ekonomi daerah terlihat dari pertumbuhan ekonomi daerah dan produktivitasnya. Oleh sebab itu, tingkat daya saing daerah diukur melalui indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, sebagai berikut.
Grafik 5.19.
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2004 – 2011
(dalam Rupiah)
Sumber: Diolah dari data Badan Pusat Statistik Nasional, 2012.
Berdasarkan grafik 5.19. terlihat adanya peningkatan PDRB Sumatera Barat secara bertahap pada setiap tahunnya. Dalam rentang tahun 2004 sampai 2011, PDRB Sumatera Barat meningkat sebesar 164,78% dari Rp. 27.358.645, 93,- menjadi Rp. 98.917.269, 39,-.
Rp37,358,645.93
Rp44,674,569.24
Rp53,029,588.21
Rp59,799,045.30
Rp70,954,515.42Rp76,752,937.71
Rp87,221,254.06
Rp98,917,269.30
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
DAMPAK PENERAPAN NILAI ADAT ... | 211
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Perkembangan persentase peningkatan tersebut dapat digambarkan dari grafik berikut.
Grafik 5.20. Perkembangan Persentase Peningkatan PDRB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2011
(dalam %)
Sumber: Diolah dari data Badan Pusat Statistik Nasional, 2012.
Berdasarkan grafik 5.20. terlihat adanya penurunan tajam
persentase PDRB Sumatera Barat dari tahun 2008 ke tahun 2009 sebesar 10,48%. Penurunan ini diakibatkan terjadinya bencana alam pada 30 September 2009 yang berpengaruh besar pada laju perkembangan perekonomian. Terlepas dari kondisi tersebut, PDRB Sumatera Barat kembali mengalami peningkatan secara bertahap. Peningkatan ini mengindikasikan semakin membaiknya kualitas pelayanan pemerintah dalam mendorong peningkatan produksi daerah dalam bidang perdagangan dan jasa. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses manajemen yang membawa pesan kebijakan kepala daerah langsung kepada walinagari mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Secara umum, 4 aspek pelayanan pemerintah di Sumatera Barat cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pemerintah semakin meningkat di Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi sistem pemerintahan nagari dalam bentuk yang lebih moderat di Sumatera Barat memiliki dampak positif terhadap perkembangan dan pembangunan di
19.58%18.70%
12.77%
18.65%
8.17%
13.64% 13.41%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
212 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Sumatera Barat. Dampak positif ini disebabkan adanya hubungan yang lebih cepat antara kepala daerah dengan walinagari sebagai kepala pada unit pemerintahan terendah. Sistem pemerintahan nagari di Sumatera Barat memangkas hubungan antar tingkat pimpinan unit pemerintahan. Walinagari diangkat langsung oleh dan bertanggung jawab kepada bupati. Walinagari tidak berada di bawah camat, karena hubungan di antara keduanya adalah kemitraan sejajar.
B. Kesejahteraan Masyarakat
Nagari dalam konteks masyarakat hukum adat Minangkabau tidak hanya dipandang sebagai sebuah sistem pemerintahan belaka, namun lebih direpresentasikan sebagai komunitas yang mempunyai hubungan keterkaitan kekeluargaan. Hal ini juga berkaitan dengan pertimbangan karakter dasar komunitas nagari di Minangkabau yang egaliter, besifat otonom dan mempunyai keunikan sendiri dalam aspek budaya. Oleh sebab itu, upaya pemekaran nagari harus diputuskan sepenuhnya oleh warga nagari yang bersangkutan. Campur tangan politik pihak luar yang bersifat top down dikhawatirkan hanya akan menimbulkan hasil yang kontraproduktif dengan nilai-nilai dasar yang terdapat dalam masyarakat hukum adat Minangkabau.
Pemikiran ini menjadi sangat urgen guna mereduksi kemungkinan hilangnya aspek-aspek sosio-kultural yang mungkin muncul di kemudian hari. Oleh sebab itu, pemekaran wilayah nagari di Sumatera Barat harus lebih dominan didorong berdasarkan aspirasi seluruh masyarakat yang ada dalam nagari beserta perangkat pemerintahannya dan juga tidak menutup kemungkinan akan keterlibatan para perantau di luar daerah. Faktor yang juga harus mendapat perhatian besar dalam pemekaran wilayah nagari adalah tingkat kesejahteraan masyarakat dan status simbol-simbol material asli nagari seperti; mesjid, tanah ulayat, tanah wakaf dan lain sebagainya. Pengabaian aspek ini berpotensi menimbulkan friksi sosial di kemudian hari, mengingat bahwa pada saat ini masalah tanah menjadi sangat krusial di Minangkabau khususnya dan di Indonesia pada umumnya terkait dengan keberadaan serangkaian regulasi yang mengatur masalah penanaman modal asing.
Kajian mengenai pemanfaatan tanah dalam nagari, baik yang dimiliki secara perseorangan ataupun komunitas hukum adat mempunyai pengaruh terhadap sistem finansial dalam nagari. Mengingat letak geografis Provinsi Sumatera Barat berada daerah tropis dan mempunyai potensi unggul dalam pertanian, pembahasan mengenai pemanfaatan tanah dalam nagari menjadi topik yang dibahas secara kompleks pada Musyawarah Adat yang dilaksanakan di Solok pada tahun 2012. Sebagai
DAMPAK PENERAPAN NILAI ADAT ... | 213
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
gambaran pola pemanfaatan tanah di Sumatera Barat, dapat diperhatikan dari grafik berikut .
Grafik 5.21. Pemanfaatan Tanah Sebagai Kawasan Lindung & Budidaya
Di Sumatera Barat Tahun 2012 (dalam km2)
Sumber: Badan Pertanahan Nasional Sumatera Barat, 2012.
0.00
0.33
4.34
2.63
83.10
6.64
320.00
674.00
394.56
1,075.45
3,230.60
1,698.60
730.74
292.00
399.95
1,527.93
3,068.67
3,399.44
2,087.55
73.36
80.10
20.90
20.37
190.35
51.00
329.96
3,213.37
2,566.57
2,270.75
717.03
1,655.70
1,501.56
1,036.00
936.45
1,602.87
669.33
2,395.51
3,923.80
Kota Pariaman
Kota Payakumbuh
Kota Bukittinggi
Kota Padangpanjang
Kota Sawahlunto
Kota Solok
Kota Padangpanjang
Kab. Pasaman Barat
Kab. Dharmasraya
Kab. Solok Selatan
Kab. Pasaman
Kab. 50 Kota
Kab. Agam
Kab. Pdg Pariaman
Kab. Tanah Datar
Kab. Sijunjung
Kab. Solok
Kab. Pesisir Selatan
Kab. Kep. Mentawai
Kawasan Budidaya
Kawasan Lindung
214 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Merujuk pada grafik 5.21. terlihat bahwa lahan budidaya mempunyai persentasi yang lebih luas daripada kawasan lindung. Jika diakumulasikan, 23.255,77 km2 atau atau sekitar 54,98% dari wilayah Provinsi Sumatera Barat merupakan lahan budidaya yang dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan. Tingginya angka lahan potensial ini mempengaruhi mayoritas mata pencarian penduduk di Sumatera Barat. Hal juga ditemukan dalam persentase mata pencaharian penduduk di Sumatera Barat, sebagai berikut.
Grafik 5.22. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Sumatera Barat
Tahun 2009 – 2012
Sumber: Sumatera Barat Dalam Angka, 2012.
45.39%
6.65%
4.41%
20.76%
5.74%
14.34%
2.80%
44.10%
6.78%
5.11%
19.90%
4.98%
16.63%
2.51%
39.30%
7.39%
6.18%
21.33%
5.17%
19.79%
3.84%
Pertanian
Industri
Bangunan
Perdagangan
Angkutan
Jasa
Lainnya
2011
2010
2009
DAMPAK PENERAPAN NILAI ADAT ... | 215
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Berdasarkan grafik 5.22. terlihat bahwa dalam 3 tahun terakhir, lapangan pekerjaan utama didominasi oleh bidang pertanian, perdagangan dan jasa. Kajian mengenai kondisi penduduk dan mata pencahariannya tidak dapat dilepaskan dari konsepsi kesejahteraan sosial. Secara sederhana, kata sejahtera diartikan dengan aman, sentosa dan makmur. Dalam artian sempit, kesejahteraan tersebut meliputi keamanan, keselamatan dan kemakmuran.17 Sementara itu, kata sosial yang diasosiasikan dengan sektor kesejateraan sosial secara sederhana diartikan sebagai suatu bidang atau atau bagian dari pembangunan sosial atau kesejahteraan rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, terutama yang dikategorikan dengan kelompok yang tidak beruntung dan kelompok yang rentan. Kesejahteraan sosial yang dimaksudkan adalah masalah sosial yang terkait dengan kemiskinan, keterlantaran, ketidakberfungsian fisik dan psikis, tuna sosial, tuna susila dan kenakalan remaja.18 Kesejahteraan sosial juga seringkali dikonotasikan dengan suatu keadaan hidup yang baik,19 kebahagiaan dan kemakmuran. Para pakar ilmu sosial mendefenisikan kesejahteraan sosial dengan tinggi atau rendahnya tingkat hidup masyarakat.20
Kesejahteraan masyarakat sebagai suatu konsep yang abstrak dan multifaceted dalam kajian ini diterjemahkan dengan landasan bahwa kesejahteraan harus dikaitkan dengan proses pemberdayaan mayarakat melalui pengembangan kapasitas dan potensi seluruh anggota masyarakat yang tentu saja menghendaki adanya human capability (kemampuan manusia. Dengan pendekatan ini dapat dikatakan pula bahwa peningkatan kesejahteraan adalah upaya mengeliminir penyebab kondisi tidak sejahtera melalui peningkatan kemampuan manusia. Untuk itu terpenuhinya kebutuhan dasar manusia (basic needs) menjadi prasyarat untuk mencapai kondisi sejahtera dengan standar hidup yang layak.
Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, kesehateraan merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat baik materil ataupun spiritual yang diliputi oleh rasa takut, keselamatan
17 W.J.S. Poerwadarimta, Pengertian Kesejahteraan Manusia (Bandung:
Mizan, 1996), 126. 18 Edi Suharto, Isu-isu Tematik Pembangunan Sosial: Konsepsi dan Strategi
(Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, 2004), 35. 19 Duane Swank, Global Capital, Political Institutions and policy Change in
Developed Welfare States (New York: Cambridge University Press, 2005), 1. 20 James Midgley, Pembangunan Sosial: Perspektif Pembangunan Dalam
Kesejahteraan Sosial (Jakarta: Diperta Islam Depag RI, 2005), 20.
216 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
kesusilaan dan ketenteraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap masyarakat untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan pancasila. Pada dasarnya, untuk mendefenisikan kesejahteraan harus menggunakan rumusan yang multidimensi.21 Hal dikarenakan ada beberapa dimensi yang membentuk kesejahteraan masyarakat. Merujuk konsepsi tersebut, dapat diperhatikan beberapa faktor yang menjadi indikator dalam menentukan tinggi rendahnya kesejahteraan masyarakat.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau yang dikenal juga dengan Human Development Index (HDI) merupakan pengukuran perbandingan harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Sebelum melihat perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat, terlebih dahulu diperhatikan perkembangan jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat, sebagai berikut.
21 Berdasarkan riset-riset akademik dan sejumlah inisiatif kongkrit yang
dikembangkan di seluruh dunia, dapat diidentifikasikan beberapa dimensi pokok yang harus dipertimbangkan secara simultan dalam membentuk kesejahteraan masyarakat. Dimensi-dimensi tersebut terkait dengan standar hidup material (seperti pendapatan, konsumsi dan kekayaan), kesehatan, pendidikan, aktivitas individu termasuk bekerja, suara politik dan tata pemerintahan, hubungan dan kekerabatan sosial, lingkungan hidup serta ketidakamanan baik yang bersifat ekonomi ataupun fisik. Joseph E. Stiglitz, et. all., Mengukur Kesejahteraan: Mengapa Produk Domestik Bruto Bukan Tolok Ukur Yang
Tepat Untuk Menilai Kemajuan (Jakarta: Marjin Kiri, 2011), 19-20. Pada awalnya, buku ini merupakan laporan kerja Commision on the Measurement of Economic Performance
and Social Progress (Commission sur la Mesure de la Performance Économique et du
Progrès Social) tahun 2009. Anggota komisi ini adalah Joseph E Stiglitz, Amartya Sen an Jean-Paul Fittousi.
DAMPAK PENERAPAN NILAI ADAT ... | 217
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Grafik 5.23. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2008 – 2012 (dalam 1000 Jiwa)
Sumber : Diolah dari publikasi BPS Nasional, 2012.
Berdasarkan grafik 5.23. di atas terlihat bahwa jumlah penduduk
miskin cenderung mengalami penurunan. Antara tahun 2007 hingga tahun 2009, jumlah penduduk miskin cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2010, angka kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 0,16%. Hal disebabkan meningkatnya jumlah penduduk miskin di desa sebesar 3,29%, meskipun penduduk miskin di kota mengalami penurunan sebesar 8,29%. pada tahun 2011, jumlah penduduk miskin kembali mengalami peningkatan sebesar 2,81% dan kembali penurunan pada tahun 2012 sebesar 8,46%. Secara umum, antara tahun 2007 dan tahun 2012, jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat mengalami penurunan sebesar 23,53% dari 529.200 jiwa menjadi 404.700 jiwa. Jika dihubungkan
149.20127.30
115.80 106.20
140.49127.80
380.00
349.90
313.50 323.80301.59
276.90
529.20
477.20
429.30 430.00442.08
404.70
2007 2008 2009 2010 2011 2012Kota Desa Kota+Desa
218 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
dengan perkembangan jumlah penduduk, maka perkembangan persentase penduduk miskin di Sumatera Barat dapat diperhatikan dalam grafik berikut.
Grafik 5.24.
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Sumatera Barat Tahun 2007 – 2012 (dalam persen)
Sumber: Diolah dari publikasi BPS Nasional, 2012.
Berdasarkan grafik 5.24. di atas, terlihat bahwa persentase penduduk miskin di Sumatera Barat cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2010, persentase penduduk miskin di desa mengalami peningkatan sebesar 0,28%. Kondisi yang sama juga terjadi pada penduduk miskin di kota pada tahun 2011 yang mengalami peningkatan sebesar 0,58%. Secara umum, antara tahun 2007 dan tahun 2012, Provinsi Sumatera Barat berhasil menurunkan persentase penduduk
9.78%
8.30%
7.50%6.84%
7.42%
6.45%
13.01%
11.91%
10.60%10.88% 10.70%
8.99%
11.90%
10.67%
9.54% 9.50%9.04%
8.00%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Kota Desa Kota+Desa
DAMPAK PENERAPAN NILAI ADAT ... | 219
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
miskin sebesar 3,90%, dari angka 11,90% menjadi 8%. Jika dihubungkan dengan perkembangan perekonomian, maka perkembangan garis kemiskinan di Sumatera Barat dapat diperhatikan dari grafik berikut.
Grafik 5.25.
Perkembangan Garis Kemiskinan di Sumatera Barat Tahun 2007 – 2012 (dalam Rupiah)
Sumber: Diolah dari publikasi BPS Nasional, 2012.
Berdasarkan grafik 5.25. di atas terlihat bahwa garis kemiskinan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh nilai tukar rupiah dan beberapa faktor ekonomi lainnya. Secara umum, antara tahun 2007 hingga tahun 2012 terjadi peningkatan garis kemiskinan sebesar 61,65% dari Rp. 160.889,- pada tahun 2007 menjadi Rp. 292.052,- pada tahun 2012.
Rp213,942.00Rp226,343.00
Rp248,525.00Rp262,173.00
Rp293,018.00
Rp321,128.00
Rp163,301.00
Rp179,755.00
Rp201,257.00Rp214,458.00
Rp241,924.00
Rp273,655.00
Rp180,669.00
Rp195,733.00
Rp217,469.00Rp230,823.00
Rp261,719.00
Rp292,052.00
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Kota
Desa
Kota+Desa
220 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin serta garis kemiskinan tidaklah secara utuh menggambarkan tingkat kesejahteraan dalam masyarakat. oleh sebab itu, perlu juga diperhatikan beberapa aspek pendukung lainnya, seperti tingkat Indeks Pembangunan Manusia, sebagai berikut :
Grafik 5.26.
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat & Indonesia Tahun 1996 – 2011
Sumber: Diolah dari data BPS Nasional, 2012.
69.20
65.80
67.50
70.5071.19
71.6572.23
72.9673.44
73.7874.28
67.70
64.30
65.80
68.70
69.5770.10
70.5971.17
71.7672.27
72.77
1996 1999 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
IPM Sumatera Barat
IPM Indonesia
DAMPAK PENERAPAN NILAI ADAT ... | 221
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Berdasarkan grafik 5.26. terlihat bahwa IPM Provinsi Sumatera Barat selalu berada pada posisi di atas rata-rata IPM Indonesia. Secara bertahap, IPM baik di Indonesia ataupun Provinsi Sumatera Barat selalu mengalami peningkatan. Jika dihubungkan dengan transformasi bentuk sistem pemerintahan di Sumatera Barat, dapat dibandingkan IPM pada masa pemerintahan desa (tahun 1996 dan 1999) dengan IPM pada era pemerintahan nagari (tahun 2002 hingga tahun 2011). Dengan tidak mengenyampingkan beberapa faktor pendukung lainnya dalam pengukuran IPM, terlihat bahwa ada perbedaan yang cukup signifikan dan bertahap antara IPM pada masa pemerintahan desa dengan IPM pemerintahan nagari di Sumatera Barat. Jika diperhatikan secara seksama, IPM Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2004 hingga data terakhir tahun 2011 selalu berada di atas kisaran angka 70.
Merujuk pada grafik 5.26. juga terlihat bahwa masyarakat hukum adat Minangkabau lebih sejahtera pada masa pemerintahan nagari. Hal ini dapat dimaklumi karena adanya pengaruh perkembangan pada beberapa sektor lainnya seperti perpolitikan, teknologi, informasi dan lain sebagainya. IPM Provinsi Sumatera Barat tahun 2011 berada pada angka tertinggi (74,15) dan berbanding lurus dengan IPM Indonesia (72,77). Ada beberapa indikator yang merincikan tingkat IPM di Sumatera Barat tahun 2011, sebagai berikut.
222 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Tabel 5.8. Persebaran Variabel IPM Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2011
Kabupaten / Kota
Angka Harapan
Hidup (Tahun)
Angka Melek Huruf
(Persen)
Rata-rata Lama
Sekolah (Tahun)
Pengeluaran Perkapita
Disesuaikan (Ribu Rupiah)
IPM
Kab. Kepulauan Mentawai 68,54 93,58 6,51 609,53 69,02 Kab. Pesisir Selatan 67,59 94,92 8,12 630,09 71,58
Kab. Solok 66,95 97,19 8,03 628,47 71,53 Kab. Sijunjung 67,25 94,78 7,50 636,43 71,38
Kab. Tanah Datar 71,30 97,10 8,35 631,37 71,39 Kab. Padang Pariaman 69,01 94,51 7,31 633,02 71,90
Kab. Agam 69,23 97,85 8,50 631,96 73,57 Kab. 50 Kota 68,81 98,85 7,94 612,36 71,60
Kab. Pasaman 67,77 98,73 7,61 642,75 73,12 Kab. Solok Selatan 64,74 97,53 7,82 616,47 69,30 Kab. Dharmasraya 66,25 97,27 8,24 610,06 69,89
Kab. Pasaman Barat 65,41 98,20 8,00 623,92 70,53 Kota Padang 71,14 99,49 10,92 649,08 78,10 Kota Solok 69,86 98,51 10,43 637,85 75,94
Kota Sawahlunto 71,86 98,55 9,14 625,98 75,19 Kota Padang Panjang 71,66 99,30 10,25 647,98 77,76
Kota Bukittinggi 71,69 99,92 10,50 653,95 78,56 Kota Payakumbuh 70,78 99,18 9,66 638,92 76,11
Kota Pariaman 69,25 98,92 9,90 631,15 74,79 SUMATERA BARAT 67,76 97,09 8,48 638,13 74,15
Sumber : BPS Sumatera Barat, 2012.
DAMPAK PENERAPAN NILAI ADAT ... | 223
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Berdasarkan tabel 5.8. terlihat bahwa daerah kotamadya mempunyai kisaran angka rata-rata di atas kabupaten. Hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti pada umumnya seluruh sarana dan prasarana baik dalam bidang pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya berpusat pada kotamadya. Hal ini juga didukung oleh kondisi wilayah yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan wilayah kabupaten. Hal ini dapat dimaklumi mengingat adanya beberapa perbedaan yang mendasar dari karakteristik sosiologis masyarakat pedesaan yang berada pada sebagian wilayah kabupaten atau dalam nagari jika dibandingkan dengan karakteristik sosiologis masyarakat perkotaan. Guna analisis lebih lanjut, menarik untuk disimak perkembangan IPM Sumatera Barat jika dihubungkan dengan fenomena pemekaran wilayah yang terjadi, sebagai berikut.
Grafik 5.27.
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009 - 2011
Sumber: BPS Sumatera Barat, 2012.
Berdasarkan grafik 5.27. terlihat bahwa IPM Sumatera Barat mengalami peningkatan. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya dorongan pada indikator angka melek huruf dan pengeluaran perkapita. Sementara itu, indikator angka harapan hidup dan rata-rata
73.44
73.78
74.28
2009 2010 2011
224 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
lama sekolah tidak begitu mengalami peningkatan yang berarti. Meskipun demikian, secara umum dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan di Sumatera Barat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jika dibandingkan antara kontribusi dalam variabel yang diberikan oleh kabupaten dan kotamadya, dapat diperhatikan dalam grafik berikut.
Grafik 5.28. Perbandingan Rata-rata Variabel IPM Antara Kabupaten dengan Kotamadya
di Sumatera Barat Tahun 2012
Sumber: Diolah dari publikasi data BPS Sumatera Barat, 2012.
70.8999.12
10.11
640.70
76.6467.74
96.71
7.83
676.53
71.23
Angka Harapan Hidup (Tahun)
Melek huruf (%) Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)
Rata-rata Pengeluaran
(Ribu Rupiah)
IPM
Rata-rata Kota
Rata-rata Kabupaten
DAMPAK PENERAPAN NILAI ADAT ... | 225
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Berdasarkan grafik 5.28. terlihat bahwa daerah kotamadya lebih dominan memberikan kontribusi terhadap pengingkatan IPM Provinsi Sumatera Barat dibandingkan daerah kabupaten. Daerah kabupaten mempunyai rata-rata pengeluaran yang lebih tinggi dibanding daerah kotamadya. Hal ini disebabkan karena luasnya wilayah dalam kabupaten sehingga dalam proses kehidupan juga membutuhkan biaya transportasi yang tinggi. Kondisi ini berbanding terbalik dengan wilayah kotamadya yang relatif lebih kecil daripada wilayah kabupaten.
Berdasarkan realitas di lapangan juga ditemukan bahwa hampir seluruh wilayah kabupaten, kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah bertransformasi menjadi bentuk pemerintahan nagari setelah ditetapkannya Perda Nomor 9 Tahun 2000 jo. Nomor 2 Tahun 2007 tentang Nagari. Kondisi ini berbanding terbalik dengan realitas pada wilayah kotamadya. Seluruh kotamadya masih menggunakan sistem pemerintahan desa dalam bentuk kelurahan.22 Implementasi sistem pemerintahan desa dalam bentuk kelurahan dengan wilayah yang relatif lebih kecil dibanding wilayah nagari lebih efektif dalam meningkatkan IPM dalam masyarakat. Pada kondisi ini, dapat disimpulkan bahwa efektivitas implementasi pememerintahan terendah berbanding terbalik dengan luas wilayah yang dicakupinya.
Merujuk kepada hasil penelitian Hengki Andora di Kota Pariaman,23 ada beberapa alasan yang menghambat penerapan sistem pemerintahan nagari pada daerah kota, sebagai berikut. a. Masyarakat merasa nyaman dengan sistem pemerintahan desa (status
quo). Hal dikarenakan penerapan sistem pemerintahan nagari yang sudah cukup lama ditinggalkan, sehingga sistem pemerintahan desa telah mengakar kuat dalam masyarakat desa.
22 Meskipun demikian, ada 2 wilayah kotamadya di Sumatera Barat yang masih
menerapkan sisitem pemerintahan desa, yaitu Kotamadya Sawahlunto dan Kotamadya Pariaman. Meskipun demikian, nagari tetap eksis dalam pemerintahan di Kotamadya Pariaman. Nagari tidak lagi menjadi bagian sistem pemerintahan, namun dipandang sebagai sistem adat yang berada dalam kewenangan KAN. Hingga saat ini, ada 12 nagari adat yang berada dalam Pemerintahan Kotamadya Pariaman. Hengki Andora, “Desa Sebagai Unit Pemerintahan Terendah di Kota Pariaman”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol-2, Nomor 1 (2011): 30-31. Nagari selaku sistem pemerintahan asli masyarakat hukum adat Minangkabau pada awalnya, berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2000, memang hanya diproyeksikan untuk diimplementasikan pada daerah kabupaten saja. Upaya implementasi ini mengalami pergeseran dengan ditetapkannya Perda Nomor 2 Tahun 2007. Merujuk kepada regulasi ini, peluang untuk menerapkan sistem pemerintahan nagari juga akan diimplementasikan pada wilayah kotamadya, meskipun sampai satt ini belum ada satu wilayah kotamadya pun yang menerapkannya.
23 Hengki Andora, “Desa Sebagai Unit”, 34-35.
226 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
b. Penerapan sistem pemerintahan nagari berakibat pada berkurangnya dana alokasi dari pemerintah yang diakibat karena kemungkinan adanya penggabungan beberapa desa menjadi sebuah nagari terkait dengan luas wilayah dalam satuan nagari. Jika penggabungan ini terjadi, maka pemerintahan desa saat ini hanya akan berada pada tingkat korong dalam pemerintahan nagari, sehingga alokasi dana semakin jauh berkurang dari yang sudah diterima pada saat ini.
c. Tingginya tingkat heterogenitas masyarakat yang mendiami daerah kotamadya. Wilayah kotamadya seringkali diidentikkan dengan pusat kemajuan. Hal ini berimplikasi pada tingginya tingkat urbanisasi penduduk. Intensitas urbanisasi penduduk berakibat pada meningkatnya persentase heterogenitas masyarakat yang tinggal di kotamadya yang berdampak pada sulitnya menerapkan sistem pemerintahan nagari yang didasari oleh faktor-faktor genealogis.
d. Hilangnya jabatan publik sebagian anggota masyarakat yang sudah duduk dalam sistem pemerintahan desa. Perubahan sistem pemerintahan desa menjadi nagari berimbas juga pada hilangnya jabatan-jabatan publik yang sudah lama ada. Kondisi ini tentu saja tidak diinginkan oleh sebagian besar elit politik pada tingkat desa.
Efektivitas sistem pemerintahan desa dalam meningkatkan IPM
masyarakat dapat dijadikan salah satu alasan dan rasionalisasi yang mendorong untuk diadakannya pemekaran wilayah. Meskipun demikian, bukanlah berarti bahwa sistem pemerintahan desa jauh lebih efektif jika diterapkan di daerah Sumatera Barat. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan terkait karakteristik dasar yang ada dalam desa dan nagari itu sendiri. Desa-desa yang berada di luar pulau Jawa seperti halnya nagari di Sumatera Barat didasarkan atas adanya hubungan darah (genealogis).24
24 Kajian mengenai klasifikasi desa berdasarkan aspek genealogis dan geologis
secara rinci dapat ditemukan dalam Soetardjo Kartohardikoesoemo, Desa (Bandung: Sumur, 1953), 44-47. Bandingkan dengan R. Bintarto, Interaksi Desa-Kota (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 46-47. Untuk penjelasan lebih lanjut terkait proses awal terbentuknya desa, bisa disimak dalam Selo Soemardjan, “Otonomi Desa Adat”, dalam Jurnal Antropologi Indonesia, 65 (2001): 121-165. Untuk konteks nagari di Sumatera Barat, hal ini dapat dipahami dari proses terbentuknya sebuah nagari. Pijakan awal terbentuknya nagari di Sumatera Barat didasarkan pada nilai-nilai kekerabatan yang mutlak harus ada dalam nagari. Hal ini tentu saja sangat jauh berbeda dengan konsep awal terbentuknya desa-desa di Pulau Jawa, dengan tidak mengabaikan beberapa pendapat yang menyatakan bahwa sebenarnya desa itu adalah bentukan masyarakat India seperti yang diungkapkan van den Berg dan Kern, atau pendapat lain yang menyatakan bahwa desa merupakan bentukan asli Indonesia seperti yang dilontarkan van Vollenhoeven, de Loouter, Brandes dan Lienfrinck.
DAMPAK PENERAPAN NILAI ADAT ... | 227
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Hal ini jauh berbeda dengan integritas desa-desa yang ada di pulau Jawa yang lebih didasarkan pada ikatan hubungan kedaerahan. Implikasinya, integritas masyarakat yang dihubungkan dengan adanya keterkaitan hubungan darah (genealogis) memiliki hukum adat yang lebih kuat dan dipatuhi jika dibandingkan dengan integritas masyarakat yang disatukan karena hubungan kedaerahan. Perbedaan karakteristik ini terkait dengan kemungkinan pemekaran wilayah di Sumatera Barat. Oleh karena itu fenomena pemekaran wilayah nagari di Sumatera Barat mempunyai kaitan yang erat dengan susunan kekeluargaan dan adat-istiadat yang terkait di dalamnya. C. Penyelesaian Konflik dan Sengketa
Aspek penyelesaian sengketa merupakan bagian penting dalam sistem pemerintahan nagari. Pada dasarnya, budaya penyelesaian konflik melalui musyawarah atau konsiliasi merupakan nilai yang banyak dianut di Indonesia.25 Budaya musyawarah, sebagai sistem nilai yang dihayati oleh masyarakat Indonesia, memerlukan tokoh yang dihormati untuk memimpin musyawarah guna tercapainya kemufakatan bersama. Apa yang diputuskan dalam musyawarah tersebut dalam prosesnya akan menjadi hukum adat.26 Dalam masyarakat Minangkabau, ninik mamak diberikan peluang yang lebih luas untuk menyelesaikan berbagai sengketa atau konflik yang melibatkan anak kemenakannya. Proses penyelesaian sengketa seperti ini dikenal dengan konsep restorative justice.
Pakar hukum pidana mempunyai berbagai pandangan dalam mendefenisikan restorative justice. Persatuan Bangsa-bangsa (PBB), sebagaimana yang diungkapkan McCluskey,27 mendefenisikan restorative
justice sebagai sebuah pendekatan penyelesaian masalah tindak kejahatan
25 Trisno Raharjo, “Mediasi Pidana dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat”,
dalam Jurnal Hukum, Volume 17, Nomor 3 (2010): 493. Lihat juga dalam Desi Tamarasari, “Pendekatan Hukum Adat dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat pada Daerah Otonom”, dalam Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 2, Nomor 1 (2002): 39. Perkembangan hukum adat di Indonesia dalam upaya penyelesaian konflik melalui musyawarah diarahkan untuk harmonisasi dalam masyarakat dengan tidak memperuncing keadaan dan sedapat mungkin menjaga suasana perdamaian. Sudargo Gautama, “Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif (ADR)”, dalam Prospek dan
Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia: Mengenang Alm. Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, S.H., L.L.M., ed. Hendarmin Djarab (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 124.
26 Adi Sulistyo, Mengembangkan Paradigma Non-Ligitasi di Indonesia (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2006), 367.
27 G. McCluskey, et. all., “I was Dead Restorative Today: From Restorative Justice to Restorative Approach in School”, dalam Cambridge Journal of Education, Volume 38, Nomor 2 (2008): 200.
228 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
dengan fokus upaya restorasi atau pemulihan dan perbaikan terhadap kerusakan serta kerugian yang dilakukan oleh pelaku tindak kriminal dengan mengadakan perluasan kemungkinan dengan melibatkan korban, pelaku dan komunitas dalam sebuah hubungan aktif dengan perantara berdasarkan undang-undang dalam mengembangkan sebuah pemecahan masalah. Sementara itu, Bazemore dan Schiff28 berpendapat bahwa restorative justice merupakan sebuah kerangka berpikir baru yang seringkali diasosiasikan dengan community justice, transformative justice, peacemaking criminology dan relational justice. Adapun Howard Zehr29 berpendapat bahwa paradigma restorative justice lebih didasarkan pada asumsi bahwa tindak kejahatan merupakan sebuah pelanggaran yang dilakukan terhadap orang, masyarakat dan hubungan dalam masyarakat daripada pelanggaran terhadap hukum.30 Hal ini merupakan tanggapan terhadap pembahasan tindak kejahatan yang difokuskan pada diskusi bilateral dalam upaya mendapatkan sebuah konsesus tentang pemaknaan pelaku terhadap pelanggaran hukum.31 Hubungan yang lebih jauh tentang konsepsi restorasi sebagai sebuah alternatif ketiga adalah tentang apa yang terjadi, siapa yang dirugikan dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kerusakan.32 Diskusi restorative justice terkait dengan korban, pelaku dan komunitasnya lebih dititikberatkan pada upaya
28 G. Bazemore dan M. Schiff, “Restorative Community Justice: Repairing
Harm and Transforming Communities” dalam Understanding Restorative Community
Justice: What and Why Now?, eds. G. Bazemore, et. all. (Cincinnati Oklahoma: Anderson Publishing, 2001), 7.
29 Cristin N. Popa, “Restorative Justice: A Critical Analysis”, dalam Law
Review, Volume 2, Nomor 4 (2012): 2. Keterangan lebih lanjut bisa ditemukan dalam Howard Zehr, Changing Lenses: A New Focus For Crime and Justice (Scottsadle, Pennsylvania: Herald Press, 1990), 181.
30 Dalam kenyatannya, perkembangan ini tidak terlepas dari pandangan ilmu kriminologi yang melihat adanya perkembangan dalam melihat pelaku tindak pidana, pendefenisian tindak pidana dan respon yang terjadi dalam sebuah tindak pidana. Meskipun tidak dapat dinyatakan bahwa pandangan kriminologi baru adalah sama dengan pandangan restorative justice, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran keduanya berdampak pada perubahan paradigma yang diakibatkan perkembangan permikiran ini. Keterangan lebih lanjut bisa disimak dalam Koesriani Siswosoebroto, Pendekatan Baru Dalam Kriminologi (Jakarta: Universitas Trisakti Press, 2009).
31 T.G. Okimoto, et. all., “Beyond Retribution: Conceptualizing Restorative Justice and Exploring Its Determinants”, dalam Soc Just Res, 22 (2009): 156.
32 G. McCluskey, et. all. “I was Dead Restorative Today”, 201.
DAMPAK PENERAPAN NILAI ADAT ... | 229
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
perbaikan dan pemulihan33 terhadap kerusakan dibandingkan pemberian hukuman. Pada tatanan praktis di Sumatera Barat, 34 restorative justice
diartikan dengan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan dirubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi korban dan pelaku.
Kajian mengenai restorative justice mulai dikembangkan oleh Barnett dan Eglash yang melakukan analisis terhadap teori dan penerapan konsep pemulihan. Mereka beranggapan bahwa prinsip-prinsip restorative justice sudah mulai diterapkan pada masa lalu oleh masyarakat tradisional dalam lingkungan adatnya.35 Paradigma penghukuman digantikan dengan salah satu konsep pemulihan. Hingga saat ini, tindak kejahatan telah dimaknai ulang sebagai sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, bukan terhadap masyarakat. Konsep ini berlaku dalam penerapan hukum adat pada beberapa wilayah di Indonesia. Menguatnya aspirasi dan keinginan untuk mengembalikan hukum ke posisinya yang semula dilatarbelakangi oleh krisis kepercayaan terhadap hukum nasional. Krisis kepercayaan ini semakin menguat karena adanya pengingkaran pemerintah pusat36 terhadap keragaman hukum dalam komunitas masyarakat hukum adat yang tercermin dalam pemaksaan unifikasi hukum. Lebih lanjut lagi, Soerjono Soekanto37 menyatakan bahwa aturan-aturan adat kerap memiliki sanksi apabila terjadi pelanggaran. Adanya sanksi bagi pelanggar ini pada dasarnya bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti semula sebelum pelanggaran tersebut terjadi.
Hukum adat di Indonesia pada dasarnya mempunyai pola yang sama dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam masyarakat.
33 Fadjar I. Thufail, “The Social Life of Reconciliation: Religion and The
Struggle for Social Justice in Post-New Order Indonesia”, dalam Working Paper No. 127 Max Planck Institute For Social Anthropology (Halle/Salee, 2010), 1.
34 Pasal 1 angka 23 Standar Operasional Prosedur tentang Mediasi Penyelesaian Perkara atau Restorative Justice Perkara Pidana Pada Tingkat Penyidikan di Lingkungan Polres Pariaman, 2013.
35 Pemahaman lebih lanjut dapat disimak dalam R. Barnett, “Restitution: A New Paradigm of Criminal Justice”, dalam Ethics Volume 87 (1977): 279-301. Simak juga dalam A. Eglash, “Beyond Restitution: Creative Restitution”, dalam Restitution in
Criminal Justice, eds. J. Hudson (Lexington Mass: D.C. Health, 1977). 36 Desi Tamarasari, “Pendekatan Hukum Adat”, 38. 37 Soerjono Soekanto, Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia
(Jakarta: Kurnia Esa, 1982), 10.
230 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Penyelesaian konflik harus memperhatikan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena jika hukum adat masih kuat dipertahankan dalam masyarakat maka mekanisme hukum adat akan sangat menentukan keberhasilan penanganan konflik. Meskipun pengadilan dibentuk oleh negara dan bersifat netral, namun pengadilan bukanlah satu-satunya institusi untuk menyelesaikan konflik, karena tidak selamanya pihak-pihak yang terlibat menyelesaikan konflik pada lembaga peradilan.38 Penyelesaian sengketa adat yang terkait dengan masalah perdata ditempuh melalui arbitrase, sedangkan upaya mediasi ditempuh untuk menyelesaikan sengketa antara pihak yang bersengketa dengan memilih mediator yang bersifat netral. Mediator tidaklah berfungsi untuk memberikan keputusan atau kesimpulan bagi para pihak, namun sebagai fasilitator untuk menunjang terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan dan kejujuran.39 Proses negosiasi dalam upaya pemecahan masalah, dengan melibatkan pihak luar (impartial) yang bersifat netral bertujuan untuk membantu pihak-pihak yang terlibat dalam memperoleh kesepakatan perjanjian secara memuaskan.
Merujuk pada rekomendasi Dewan Eropa Nomor R (99) 19 tentang Mediation in Penal Matters sebagaimana yang termuat dalam Explanatory Memorandum, dikenal sebuah konsep traditional village atau tribunal moots sebagai salah satu model mediasi dalam hukum pidana. Konsep ini mengharuskan seluruh anggota masyarakat untuk bertemu dalam upaya mencegah konflik dan tindak kejahatan di antara warganya. Model ini merupakan pilihan tepat untuk diterapkan dalam masyarakat gemeinschaft. Model inilah yang kemudian dikenal dengan konsep restorative justice yang mulai diterapkan dalam masyarakat hukum adat Minangkabau.
Ada beragam bentuk pendekatan peradilan restoratif yang dapat digunakan pada berbagai tingkatan dalam proses sistem peradilan pidana. Polisi selaku jalur pertama dalam sistem peradilan pidana mempunyai peran penting guna berlangsungnya upaya restorative justice. Pihak kepolisian dengan kewenangan diskresi yang dimilikinya dapat menjadi fasilitator mediasi antara pelaku, korban dan masyarakat. Mediator dapat ditunjuk berdasarkan kesepakatan antara polisi dan lembaga adat.
38 Proses pencarian keadilan tidak hanya didapatkan dalam ruang sidang
pengadilan, namun juga dapat ditemukan di luar ruang sidang pengadilan. Marc Galanter, “Keadilan di Berbagai Ruangan: Lembaga Peradilan, Penataan Masyarakat serta Hukum Rakyat”, dalam Antropologi Hukum Sebagai Sebuah Bunga Rampai, ed. T.O. Ihromi (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), 81.
39 Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan:
Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 69.
DAMPAK PENERAPAN NILAI ADAT ... | 231
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Pemberlakuan hukum adat juga merefleksikan perlindungan terhadap hak-hak korban yang diatur dalam hukum adat dengan tidak mengenyampingkan hak-hak pelaku.
Beberapa pakar40 memaknai restorative justice sebagai sebuah proses, sementara pakar lain41 berpendapat bahwa restorative justice merupakan sebuah hasil. Restorative justice merupakan proses yang ditempuh oleh seluruh pihak yang terlibat dengan titik tolok untuk menemukan solusi kolektif sebagai akibat dari adanya pelanggaran dan implikasi pada saat yang akan datang. Terhadap hal ini, Gavrielides42 menyatakan bahwa pemaknaan restorative justice sebagai sebuah proses tidaklah bersifat accidental, tetapi merupakan pilihan yang dilakukan dengan sangat berhati-hati.
Penerapan restorative justice oleh pihak kepolisian dalam tatanan masyarakat hukum adat tidaklah berlaku pada seluruh bentuk tindak pidana. Upaya restorative justice hanya berlaku pada beberapa bentuk tindak kejahatan tertentu saja. Merujuk kepada Standar Operasional Prosedur penanganan perkara pidana melalui restorative justice yang dibentuk oleh Kepolisian Resort Pariaman,43 maka dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Perkara yang menjadi perhatian secara manusiawi dan sosial,
meliputi: a. tersangka sudah lanjut usia; b. tersangka masih anak-anak berdasarkan Undang-undang Nomor
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
40 Beberapa pakar yang beranggapan bahwa restorative justice sebagai sebuah
proses di antaranya; T. Marshal dalam T. Masrhall, Alternatives to Criminal Courts: The
Potential for Non-Judicial Dispute Resolution (Brookfiled: Gower Publishing Co., 1985), P. McCold dalam P. McCold, “Paradigm Muddle: The Threat to Restorative Justice Posed by Its Merger With Community Justice”, dalam Contemporary Justice
Review, Volume 7, Nomor 1 (2004) dan Howard Zehr, The Little Book of Restorative
Justice (Intercourse: Good Books, 2002). 41 Pakar yang beranggapan bahwa restorative justice merupakan sebuah hasil
adalah K. Doolin. Pemikirannya terkait hal ini dapat ditemukan dalam K. Doolin, “But What It Does Mean? Seeking Defenitional Clarity in Restorative Justice” dalam Journal
of Criminal Law, Volume 71, Nomor 5 (2007). 42 T. Gavrielides, “Some Meta-Theoretical Questions For Restorative Justice”
dalam Ratio Juris, Volume 18, Nomor 1 (2005): 86. 43 Standar Operasional Prosedur tentang Mediasi Penyelesaian Perkara atau
Restorative Justice Perkara Pidana Pada Tingkat Penyidikan di Lingkungan Polres Pariaman, 2013. Bab 2 tentang Klasifikasi Perkara Yang Masuk Kategori Restorative
Justice, pasal 4 sampai pasal 8.
232 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
c. tersangka melakukan tindak pidana untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak dan tidak menjadikan tindak kejahatan itu sebagai mata pencaharian, dan;
d. tersangka dan korban mempunyai hubungan keluarga, tindak kejahatan murni terjadi hanya karena faktor kelalaian.
2. Perkara tindak pidana ringan dengan kerugian di bawah angka nominal Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), meliputi: a. pencurian ringan (pasal 364 KUHP); b. penggelapan ringan (pasal 373 KUHP); c. penipuan ringan (pasal 379 KUHP); d. kejahatan surat ringan (pasal 384 KUHP); e. pengrusakan ringan (pasal 407 KUHP), dan; f. penadahan ringan (pasal 482 KUHP).
3. Perkara kecelakaan lalu lintas dengan kriteria tertentu, meliputi: a. kecelakaan berkendara di jalan raya yang terjadi karena kelalaian
dan mengakibatkan korban meninggal, namun tersangka masih mempunyai hubungan keluarga dengan korban, dan;
b. kecelakaan lalu lintas yang melibatkan massa. 4. Perkara pidana yang karena pertimbangan kemanusiaan dan harus
mengedepankan prinsip pembinaan, meliputi: a. pencurian; b. penipuan; c. penggelapan; d. penadahan; e. penganiayaan, dan; f. melakukan kekerasaan secara bersama di hadapan umum.
5. Perkara yang rentan melibatkan kekuatan massa dan memicu munculnya konflik massa, meliputi: a. pengelolaan sumber daya alam; b. pembagian hasil pengelolaan sumber daya alam; c. sengketa tanah; d. sengketa politik, dan; e. SARA.
Efektivitas penerapan restorative justice terhadap masyarakat
hukum adat Minangkabau yang ada di Sumatera Barat dapat diperhatikan dalam grafik 5.29. berikut.
DAMPAK PENERAPAN NILAI ADAT ... | 233
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Grafik 5.29. Perkembangan Angka Tindak Pidana di Sumatera Barat
Tahun 2003 – 2011
*Tahun 2006 tidak ada data. Sumber: Diolah dari data Badan Pusat Statistik Nasional, 2012.
Merujuk pada grafik 5.29. terlihat bahwa angka tindak pidana di
Sumatera Barat cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya kecuali pada tahun 2004 yang mengalami penurunan sebesar 7,79% dan tahun 2010 sebesar 8.69%. Tingginya angka tindak pidana disebabkan oleh beberapa faktor. Jika hanya didasarkan pada grafik 5.24., maka kualitas pelayanan pemerintah dalam bidang keamanan belumlah dapat dikatakan mengalami peningkatan. Berdasarkan keterangan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Barat,44 realitas sosial penerapan restorative justice dalam menyelesaikan konflik dan sengketa pada dasarnya sudah berlangsung lama dan terbukti efektif dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau. Dalam pelaksanaannya, banyak perkara yang tidak diteruskan karena sudah diselesaikan melalui jalur lembaga adat dalam
44 Laporan ini disampaikan oleh Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam Musyawarah Adat yang diselenggarakan di Solok pada Maret 2012.
5,8425,387
7,203
9,499
10,776
11,848
10,81911,695
2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011
234 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
masyarakat Minangkabau.45 Perkara-perkara yang sudah diselesaikan dalam tataran adat tidak dicatatkan dan tidak dimasukkan ke dalam laporan statistik.46 Meskipun demikian, secara umum pelaksanaan restorative justice dengan melibatkan tokoh dan lembaga adat dalam masyarakat mampu mengurangi angka tindak kejahatan dan tindak pidana dalam masyarakat hukum adat Minangkabau.
D. Partisipasi Tokoh Adat dalam Pembangunan
Nagari merupakan nama tradisional dan unit politik sebuah organisasi sosial politik sejak masa pra kolonial.47 Susunan pemerintahan nagari tradisional telah mengalami intervensi dari pihak luar. Para masa awal kemerdekaan, pemerintahan nagari mengalami perubahan dengan ditetapkannya Maklumat Residen Sumatera Barat Nomor 20 dan Nomor 21 Tahun 1946 terkait dengan perubahan dalam susunan kelembagaan nagari. Titik puncak intervensi tersebut terjadi ketika ditetapkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Upaya pemerintah pusat dalam unifikasi sistem pemerintahan terendah memberikan kesan buruk terhadap perkembangan demokrasi lokal.48
45 Hal yang sama juga diungkapkan dalam Eva Achjani Zulfa, “Keadilan
Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia”, dalam Jurnal Kriminologi
Indonesia, Volume 6, Nomor 2 (2010): 187. 46 Sebagai bahan perbandingan, dapat disimak dalam Rudi Satriyo, et. all.,
Advokasi Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Jakarta: Balitbang HAM Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2006), lihat juga Peri Umar Farouk, et. all., Kembali Ke Masa Depan: Otonomi Daerah Dan Kebangkitan Adat Yang Tidak Pasti (Palangkaraya: Justice for the Poor, 2004) dan juga Dewi Novitrianti, et. all., Wet Tu Telu: Peluang Membangun Peradilan di Tingkat Desa (Lombok: Justice fo the Poor, 2004).
47 Franz and Keebet von Benda-Beckmann, “Recreating The Nagari: Decentralization in West Sumatera”, Working Paper at Max Planck Institute of Social Anthropology Halle/Yalle (2001), 9.
48 Asrinaldi, “Implementasi Demokrasi Lokal di Balik Bayang-bayang Otonomi Negara”, Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik, Tahun 25, Nomor 2 (2011): 98. Lihat juga Al Rafni, et. all., “Marginalisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Pemberdayaan Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat”, Demokrasi Volume VII Nomor 1 (2008): 17. Nagari menjadi identitas etnik Minangkabau dengan konsep pemufakatannya sendiri. Model demokrasi pemufakatan yang dilaksanakan di Minangkabau terkait dengan sistem pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan para penghulu pada tingkat suku. Padanan model demokrasi ini berkaitan dengan konsep demokrasi deliberatif yang memprioritaskan keputusan kolektif dan menghindari keputusan individualis (liberalism) yang didasarkan pada pilihan rasional. A. Gutman & D. Thompson, Why Deliberative Democracy? (New Jersey: Princeton University Press, 2004), 3. Pemaksaan ini terlihat pada adanya degradasi fungsional KAN dalam
DAMPAK PENERAPAN NILAI ADAT ... | 235
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Akibatnya, karakter sistem pemerintahan nagari yang merupakan bentuk sistem pemerintahan terendah dalam tatanan sosiokultural masyarakat Minangkabau menjadi hilang.
Menurut Manan sebagaimana yang dikutip Asrinaldi,49 ketika sistem pemerintahan desa diterapkan, partisipasi masyarakat menjadi lebih menurun jika dibandingkan dengan sistem pemerintahan nagari. Hal ini merupakan akibat dari tidak dekatnya hubungan emosional yang dibentuk dalam sistem pemerintahan desa jika dibandingkan dengan sistem pemerintahan nagari. Hal ini dapat dirasionalisasikan bahwa pada dasarnya sistem pemerintahan desa lebih menekankan pada konsep top
down dalam bentuk birokrasi dari pemerintah pusat, sehingga hubungan emosional yang terbentuk hanya terkait dengan masalah kepatuhan terhadap pemerintah. Implikasi ini sangat jauh berbeda dengan karakteristik masyarakat nagari yang lebih diidentikkan dengan susunan geopolitik yang terpengaruh oleh hubungan genealogis.
Pemaksaan implementasi sistem pemerintahan desa di Sumatera Barat mengakibatkan terjadinya guncangan budaya (culture shock) dan tidak ter-cover-nya nilai-nilai adat Minangkabau.50 Kondisi ini merupakan fakta yang terjadi meskipun pada masa ini KAN tetap diakui sebagai representasi dari masyarakat dalam nagari. Transformasi dari bentuk nagari ke bentuk desa berimbas pada perubahan struktural, orientasi dan filosofi. Pada era reformasi, bentuk pemerintahan desa dikembalikan ke bentuk pemerintahan nagari dengan alasan bahwa pemerintahan nagari lebih menghormati martabat dan hak-hak masyarakat hukum adat Minangkabau. Alasan lain pengembalian bentuk ini juga untuk mempertimbangkan dan menyelaraskan pemerintahan nagari dengan nilai demokrasi modern (otonomi daerah dan HAM) serta menyelaraskannya dengan nilai-nilai nation state Indonesia.
masyarakat hukum adat Minangkabau yang seharusnya merupakan representasi masyarakat ternyata dijadikan sebagai media untuk mendukung kebijakan pemerintah.
49 Asrinaldi, “Implementasi Demokrasi”, 99. 50 Yasril Yunus, “Model Pemerintahan Nagari yang Partisipatif dalam
Masyarakat Minangkabau”, dalam Jurnal Demokrasi, Vol-6, Nomor 2 (2007): 213. Lihat juga dalam Tengku Rika Valentina, et. all., “The State Versus Local Elite Conflict in A Transitional Phase of Democracy”, dalam International Journal of Administrative Science and Organization Vol 18 No. 2 (2011): 214. Terpecahnya sistem nagari menjadi desa menyebabkan Minangkabau seolah kehilangan trade mark-nya karena sistem pemerintahan nagari merupakan mempunyai peranan yang menyeluruh dari berbagai unsur kepemimpinan, baik unsur formal ataupun unsur nonformal. Rita Gani, “Tigo
Tungku Sajarangan: Analisis Pola Komunikasi Kelompok dalam Interaksi Pemimpin Pemerintahan di Sumatera Barat”, dalam Jurnal Mediator, Vol-7, Nomor 2 (2006): 244.
236 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Jika diperhatikan, susunan kepemimpinan dan perangkatnya dalam sistem pemerintahan desa dengan sistem pemerintahan nagari di era otonomi daerah tidak jauh berbeda. Antara regulasi pemerintahan desa dengan pemerintahan nagari pada dasarnya memiliki banyak kesamaan mendasar, sehingga jika diperhatikan sepintas terlihat bahwa seolah-olah Perda Nagari hanya melakukan labelisasi terhadap regulasi desa. Hal ini dapat dimaklumi karena keberadaan nagari sama dengan desa sebagai institusi pemerintahan terendah di Indonesia. Rasionalisasi lainnya yang harus diperhitungkan kembali, bahwa konsep dasar nagari itu sendiri adalah kesatuan genealogis dan adanya keterikatan emosional yang kuat antar sesama anggota masyarakatnya. Beberapa pertimbangan ini kemudian menjadi faktor pembeda dalam terbentuknya regulasi yang mengatur masalah nagari.
Konsep kepemimpinan yang didistribusikan dalam bidang eksekutif terdiri dari kepala pemerintahan beserta perangkatnya dan keberadaan lembaga eksekutif. Kesamaan ini juga ditemukan dari tugas dan wewenang diemban oleh masing-masing aspek kepemimpinan. Faktor pembeda dalam kepala pemerintahan hanyalah terkait dengan masa jabatan. Pada regulasi pemerintahan desa, kepala desa menjabat selama 8 tahun, sedangkan pada pemerintahan nagari, walinagari menjabat selama 6 tahun. Faktor pembeda yang lainnya adalah dari segi pengangkatan dan pertanggungjawaban. Kepala desa diangkat dan bertanggung jawab kepada camat, sedangkan walinagari diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada bupati berdasarkan rekomendasi camat.
Faktor pembeda utama di antara kedua regulasi ini adalah adanya pengakuan terhadap eksistensi institusi sosio-politik pada regulasi nagari. Perda Nagari memuat ketentuan tentang keberadaan Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai sebuah forum musyawarah tertinggi ninik mamak dan menjadi lembaga konsultatif terhadap walinagari dalam membentuk RPJMN dan beberapa peraturan lainnya yang terkait dengan masyarakat. Secara khusus, KAN bertugas dalam menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah sako dan pusako. Unsur yang terlibat dalam keanggotaan KAN adalah ninik mamak dalam nagari dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa unsur kemasyarakatan lainnya seperti alim ulama dan cadiak pandai. Jika diperhatikan secara lebih seksama, terdapat kesamaan unsur kemasyarakatan yang terlibat dalam lembaga yang ada dalam nagari lainnya, yaitu Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari).
Kesamaan unsur yang terlibat di dalamnya pada satu sisi memberikan peluang yang lebih besar terhadap keikutsertaan dan
DAMPAK PENERAPAN NILAI ADAT ... | 237
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
partisipasi tokoh-tokoh adat, cendikiawan dan tokoh agama dalam pembangunan nagari. Di sisi lain, hal ini seringkali menjadi potensi konflik dalam memperebutkan keanggotaannya sehingga tidak jarang merugikan masyarakat. BAMUS Nagari merupakan organisasi dalam nagari yang memfokuskan kegiatannya dalam berbagai hal formal dalam nagari, sementara KAN mempunyai wewenang dalam hal-hal pelestarian nilai-nilai adat. Perbedaan dalam keanggotaan di antara keduanya adalah adanya pemberian peluang bagi tokoh bundo kanduang (kaum perempuan) untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan masyarakat.
Perubahan bentuk pemerintahan desa menjadi nagari pada masa otonomi daerah mengalami pergeseran yang signifikan dari konsep nagari yang sudah ada pada masa sebelumnya. Kondisi ini diakibatkan adanya usaha untuk memodernisasi bentuk tradisional agar bisa sesuai dengan konsepsi nation state Indonesia. Upaya untuk mengembalikan sistem pemerintahan nagari pada masa otonomi daerah memunculkan konflik antara nilai-nilai adat dengan nilai-nilai modern. Konflik ini muncul dari adanya intervensi pemerintah dalam pelaksanaan sistem pemerintahan nagari. Intervensi tersebut memberikan perubahan mendasar dikarenakan adanya upaya integrasi sistem sosiobudaya masyarakat nagari ke dalam penyelenggaraan pemerintahan modern di tingkat terendah.51 Imbasnya, nagari tidak lagi menjadi pusat perkembangan sistem sosiobudaya masyarakat seutuhnya mengingat kuatnya dominasi sistem pemerintahan modern dalam nagari.
Kondisi ini merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan, mengingat pada saat ini nagari mempunyai fungsi dan wewenang ganda.52 Wewenang ganda ini dikarenakan pada satu sisi nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat dengan wewenang dan politik serta hak adat, sementara pada saat yang sama juga berkedudukan sebagai tingkat pemerintahan terendah dengan wewenang dan hak publik untuk mengelola sumberdaya alamya.
51 Jika dilihat dalam perspektif demokrasi lokal, ciri utama dalam demokrasi
lokal adalah penonjolan aspek sosiokultutal yang berkembang dalam masyarakat (cultural influence). Hal ini dikarenakan bentuk partisipasi, mekanisme keterlibatan masyarakat dan nilai yang dikembangkan dalam proses tersebut yang membedakan satu masyarakat dengan yang lain dan sudah menjadi sifat asli dari sebuah demokrasi lokal. Asrinaldi, “Implementasi Demokrasi Lokal”, 100.
52 Melinda Noer, “Pembangunan Berbasis Kelembagaan Adat: Sebuah Alternatif Pembelajaran Dari Kasus Kinerja Kelembagaan Nagari Dalam Perencanaan Wilayah Di Provinsi Sumatera Barat”, dalam Jurnal Mimbar, Vol-XXII, Nomor 2 (2006): 237.
238 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Salah satu indikator yang menunjukkan pergeseran makna sosiokultural dalam pemerintahan nagari saat ini adalah dalam proses pemilihan walinagari. Pada saat ini, walinagari dipilih secara langsung oleh masyarakat dengan menggunakan konsepsi suara terbanyak. Jika dicermati lebih lanjut, ketentuan ini jauh berbeda dengan apa yang sudah diberlakukan di nagari sebelum berubah menjadi desa. Pada masa pemerintahan nagari sebelum pemerintahan desa, walinagari dipilih dari pimpinan suku yang dituakan dan dianggap cakap untuk menjadi walinagari.53
Jika dibandingkan dengan ketentuan dalam Perda terkait persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk ikut serta mencalonkan diri menjadi walinagari, terdapat perbedaan mendasar. Perbedaan mendasar ini dapat ditinjau dari dua hal. Pertama, penggunaan metode musyawarah untuk mencapai sebuah keputusan. Pada dasarnya, masyarakat hukum adat Minangkabau mempunyai pola musyawarah sendiri dalam membentuk sebuah keputusan. Mekanisme musyawarah masyarakat hukum adat Minangkabau diwariskan dalam tiga sistem pemerintahan adat (adat kelarasan).54 Pola musyawarah ini mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan yang diambil. Sementara itu, dalam ketentuan yang dimuat dalam Perda Nagari pemilihan walinagari dilaksanakan dengan cara pemilihan langsung oleh anggota masyarakat. Kedua, berdasarkan karakterisitik dasar yang berkembang dalam
53 Muhammad Zainuddin, Implementasi Pemerintahan Nagari Berdasarkan
Hak Asal-usul Adat Minangkabau (Yogyakarta: Ombak, 2010), cet-2, 39. 54 Adat kelarasan merupakan seperangkat nilai-nilai, norma-norma dan aturan-
aturan yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar yang mengatur aktivitas dan kehidupan sosial politik masyarakat Minangkabau. Oleh sebab itu, sistem kelarasan lebih diasosiasikan sebagai sistem pemerintahan tradisional Minangkabau. Irawati, “Bundo
Kanduang dan Tantangan Politik Dalam Badan Perwakilan Anak Nagari”, Jurnal
Demokrasi, Vol-IX, Nomor 1 (2010): 39. Ada 3 sistem pemerintahan adat di Minangkabau tertuang dalam tiga bentuk. Pertama, kelarasan koto piliang yang lebih menonjolkan sistem aristokrasi dalam pemerintahan adat dikarenakan adanya peran masing-masing yang sesuai dengan kedudukannya, namun peran masing-masing unit tersebut saling terkait dalam satu kesatuan dalam membuat keputusan untuk nagari. Kelarasan ini terkenal dengan falsafahnya bajanjang naiak, bataggo turun (berjenjang naik, bertangga turun). Kedua kelarasan bodi caniago yang menonjolkan aspek kesamaan kelas dalam pemerintahan adat dengan hak suara yang sama yang tergambarkan dalam falsafah duduak samo randah, tagak samo tinggi (duduk sama rendah, berdiri sama tinggi). Ketiga kelarasan nan panjang yang menonjolkan penggabungan kedua aspek sebelumnya, namun dalam keadaan darurat pengambilan keputusan dilakukan dengan menggunakan sistem aristokrasi di mana pemimpin yang cenderung lebih berperan. Muhammad Zainuddin, Implementasi Pemerintahan Nagari
Berdasarkan Hak Asal-usul Adat Minangkabau (Yogyakarta: Ombak, 2010), cet-2, 38.
DAMPAK PENERAPAN NILAI ADAT ... | 239
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
masyarakat nagari itu sendiri. Layaknya sebagai sebuah kesatuan genealogis, proses pembentukan nagari dipengaruhi oleh eksistensi kekeluargaan di dalamnya. Figur yang disyaratkan untuk menjadi walinagari dalam Perda Nagari tidak sepenuhnya akan sama dengan sosok yang diinginkan untuk menjadi walinagari berdasarkan pemerintahan nagari sebelum masa pemerintahan desa.
Indikator lain yang menunjukkan adanya pergeseran nilai-nilai sosiokultural dalam nagari saat ini adalah eksistensi dan fungsi KAN dalam nagari. Ketentuan dalam Perda Nagari menunjukkan adanya pemisahan KAN dengan sistem pemerintahan terendah dalam menjalankan tugasnya di nagari. Pada saat ini, KAN tidak lagi menjadi bagian dari sistem pemerintahan nagari dan juga tidak lagi diidentikkan dengan sebuah sistem pemerintahan adat seperti eksistensi dan fungsinya yang terdahulu. KAN hanya menjadi simbol keberadaan unsur sosiokultural dalam masyarakat hukum adat Minangkabau dengan fungsi utama sebagai lembaga yang bertugas menyelesaikan masalah sengekta sako dan pusako. Kebijakan pemerintah daerah dalam Perda Nagari terkait pergeseran eksistensi dan fungsi KAN berakibat pada ambivalensi fungsi unsur-unsur kemasyarakatan. Ambivalensi ini terjadi karena adanya marginalisasi unsur genealogis dalam masyarakat Minangkabau.
KAN tidak hanya mempunyai fungsi internal dalam menyelesaikan masalah sengketa sako dan pusako. KAN juga berperan dalam proses akomodasi antara penduduk asli dalam nagari Minangkabau dengan para pendatang. Pada pendatang dalam konteks ini tidak hanya dalam artian penduduk dari luar Minangkabau, namun juga terhadap penduduk Minangkabau asli yang bermigrasi dari nagari asalnya. KAN mempunyai tugas dan tanggung jawab besar dalam menjaga kestabilan nilai-nilai tradisional Minangkabau. Hal ini ini terlihat dari beberapa proses minangkabauisasi pendatang dalam sebuah nagari. Dalam kegiatan ini, KAN mempunyai andil besar dalam menentukan orang tersebut layak atau tidak untuk diberikan pengakuan hubungan genealogi dengan penduduk asli dalam nagari. Meskipun fungsi ini sudah jarang dilaksanakan dalam bentuk aslinya, namun KAN tetap memegang andil besar dalam menjaga keharmonisan hubungan antara penduduk asli Minangkabau dengan pendatang dengan cara yang lebih moderat, sistematis dan formal.
Konsesus yang ditimbulkan upaya modernisasi bentuk pemerintahan nagari adalah terjadinya perubahan peta politik sosial dalam masyarakat nagari di Minangkabau. Jika pada masa pemerintahan nagari sebelum desa, orang yang duduk dalam perangkat pemerintahan nagari haruslah orang-orang yang mengerti dan paham dengan adat yang
240 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
berlaku. Seorang walinagari pada waktu itu diharuskan dari golongan ninik mamak, sementara dalam pemerintahan nagari era otonomi daerah, seorang walinagari tidak hanya orang yang mengerti tentang tatanan adat, namun juga mengerti tentang sistem pemerintahan NKRI dan perkembangan teknologi yang terjadi di dalam masyarakat. Pada sistem demokrasi pemerintahan nagari sebelum desa, nagari membuat kebijakan melalui proses muyawarah untuk mufakat sehingga kebijakan yang dihasilkan sifatnya lebih otonom. Kondisi ini berbanding terbalik dengan kondisi demokrasi dalam masa otonomi daerah yang lebih banyak dipengaruhi oleh intervensi pemerintah kabupaten. Intervensi tersebut terlihat dari tingginya ketergantungan aparat nagari terhadap petunjuk teknis. Pemerintahan nagari juga sering kali tergantung kepada pemerintahan kabupaten dalam bidang ekonomi dan alokasi dana, di samping adanya pembatasan kewenangan yang dimiliki nagari itu sendiri.
BAB VI PENUTUP
A. Kesimpulan 1. Pembentukan adat tradisional Minangkabau merupakan proses yang
panjang dengan melibatkan nilai lokal, nilai Islam dan nilai barat yang diperkenalkan oleh Belanda. Hubungan dagang yang terbentuk antara masyarakat Minangkabau dengan para saudagar Islam pada masa pra-kolonialisme menimbulkan akulturasi budaya. Hal yang paling menonjol dalam proses akulturasi tersebut adalah secara perlahan-lahan masyarakat Minangkabau mulai menganut agama Islam. Meskipun dalam perkembangan selanjutnya juga dipengaruhi oleh faktor agama Kristen yang dibawa oleh penjajah, namun keberadaan agama Kristen tidak mampu menggoyahkan keteguhan masyarakat dalam memeluk agama Islam. Pada masa awal kolonialisme, Belanda menjalankan politik pemerintah yang memberikan pengakuan terhadap masyarakat pemeluk agama Islam untuk menjalankan ajaran Islam dalam kehidupannya. Adat Minangkabau yang merupakan warisan asli Minangkabau secara turun menurun mengalami perbenturan dengan pergerakan Islam. Hal ini tergambar dari adanya gerakan purifikasi atau pemurnian ajaran Islam di Minangkabau yang berlangsung dua kali. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh pihak Belanda untuk semakin memperuncing persinggungan antara nilai-nilai adat dan Islam yang dipakai oleh masyarakat Minangkabau dalam kehidupan sehari-hari dengan memberikan pengakuan yang lebih kuat kepada hukum adat sebagai media yang menyaring nilai-nilai keislaman.
2. Rekonstruksi nilai-nilai adat dan Islam juga melalui proses saling mengisi. Puncak persinggungan adat Minangkabau dengan nilai-nilai keislaman adalah dengan ditetapkannya Sumpah Satie Bukik Marapalam. Momentum ini menjadi sebuah nota kesepahaman dan perdamaian antara golongan adat dengan golongan reformis Islam. Hal ini dinyatakan dalam falsafah adat Minangkabau yang berbunyi adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah (adat didasarkan
242 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
kepada ajaran Islam, ajaran Islam didasarkan kepada Alquran). Perjanjian ini juga yang melatarbelakangi kemunculan penolakan terhadap ide untuk menjadikan adat sebagai media penyaring nilai-nilai Islam dalam masyarakat Minangkabau dikarenakan sebagian praktek adat tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam dan ide tersebut bertujuan untuk menghalangi kemajuan Islam di Indonesia. Implikasi terhadap bantahan ini adalah menguatnya pemikiran bahwa hukum adat dapat diberlakukan apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pada masa orde baru, ide ini dikembangkan bahwa antara sistem hukum adat dan hukum Islam dapat hidup berdampingan. Ekuilibrium tersebut dapat tercapai berdasarkan fakta, baik secara teori ataupun praksisnya bahwa kedua bentuk hukum ini saling melengkapi. Hukum Islam pada dasarnya menerima nilai-nilai adat dalam proses legislatifnya, sementara hukum adat menerima hukum Islam sebagai titik kulminasi atau kesempurnaan dari sistem pribumi. Dari sisi praksisnya, peran yang dimainkan oleh hukum adat tidak pernah dikesampingkan dalam interaksi antara hukum Islam dan realitas sosialnya. Tesis ini memandang bahwa perpaduan yang terjadi antara hukum adat dengan hukum Islam telah menjadi sebuah kearifan lokal.
3. Pola rekonstruksi antara adat dengan Islam yang mengkristal dalam bentuk sistem pemerintahan nagari kembali mengemuka pada era otonomi daerah dan desentralisasi kekuasaan. Kebijakan otonomi dan desentralisiasi kekuasaan memberikan peluang dan kewenangan yang luas dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah untuk membangun daerahnya. Peluang tersebut dimanfaatkan oleh Pemerintah Sumatera Barat untuk melestarikan nilai-nilai kearifan lokal yang sudah ada sejak zaman dahulu. Hal ini terbukti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 yang kemudian diamandemen dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2007 tentang Sistem Pemerintahan Nagari. Keberadaan Peraturan Daerah ini menunjukkan upaya pemerintah daerah Sumatera Barat untuk merekonstruksi, merevitalisasi dan memodernisasi bentuk sistem pemerintahan nagari yang dahulunya sempat terhapus karena adanya upaya pemaksaan unifikasi sistem pemerintahan oleh otoritas kekuasaan era orde baru. Nagari di Minangkabau tidak hanya terkait dengan sistem pemerintahan semata. Lebih jauh lagi, nagari merupakan simbol kosmologis masyarakat hukum adat Minangkabau yang sudah mempunyai susunan dan komposisi pemerintahan yang lengkap. Tidak sedikit ahli yang menyebutkan bahwa sistem
PENUTUP | 243
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
pemerintahan nagari di masa Minangkabau tradisional sudah menyerupai sebuah republik otonom atau republik kecil.
4. Adanya formalisasi konsep pemerintahan nagari di Minangkabau tradisional disertai dengan beberapa modernisasi dan akomodasi sehingga bisa terintegrasi dengan sistem pemerintahan nasional telah memunculkan bentukan sistem pemerintahan nagari baru yang lebih moderat jika dibandingkan dengan bentuk sistem pemerintahan nagari yang sudah ada sebelumnya. Hal ini terlihat dengan adanya pengakuan kepada peranan lembaga-lembaga adat yang diduduki oleh tokoh-tokoh adat dan bertugas untuk melestarikan budaya dan menyelesaikan sengketa dalam masyarakat. Meskipun demikian, masih ditemukan adanya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap daerah terkait hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaan.
5. Implementasi sistem pemerintahan nagari di Sumatera Barat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena mempunyai hierarki kepemimpinan yang lebih sederhana daripada sistem pemerintahan desa. Dalam sistem pemerintahan nagari, walinagari diangkat dan bertanggung jawab kepada bupati berdasarkan rekomendasi camat, sehingga pesan-pesan kebijakan pemerintah pusat lebih cepat diterima dan diterapkan pada satuan pemerintahan terendah. Peningkatan kesejahteraan masyarakat terlihat dalam berbagai aspek, yaitu: kesehatan, pendidikan, ekonomi dan bidang infrastruktur perhubungan dasar. Secara umum, aspek-aspek tersebut cenderung mengalami peningkatan setiap tahun dengan laju pertumbuhan yang bervariasi. Adanya bencana gempa bumi di Sumatera Barat pada 30 September 2009 berimbas pada menurunnya beberapa sektor strategis dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat. Namun setelah tahun 2009, sektor-sektor tersebut kembali berkembang dan kembali mengalami tren peningkatan seperti tahun-tahun sebelumnya. Fenomena pemekaran wilayah nagari di Sumatera Barat diakibatkan adanya diferensiasi nagari dalam pengakuannya pada sistem pemerintahan nasional. Pemekaran wilayah nagari harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan genealogis, bukan hanya berdasarkan pertimbangan luas wilayah. Pemekaran wilayah nagari juga berimbas pada adanya pembukaan jalan baru yang menghubungkan nagari-nagari baru.
6. Pengakuan secara nasional terhadap kedudukan dan fungsi tokoh adat, tokoh agama, cendikiawan dan tokoh perempuan yang diwadahi dalam BAMUS Nagari dan KAN memberikan peluang yang lebih besar kepada tokoh-tokoh tersebut untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan. Tokoh-tokoh tersebut mempunyai peran penting dalam
244 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
upaya penyelesaian konflik dan sengketa yang terjadi antar sesama anggota masyarakat. Tokoh masyarakat juga berperan dalam proses akomodasi antara penduduk asli dalam nagari Minangkabau dengan para pendatang guna menjaga kestabilan nilai-nilai tradisional Minangkabau. Eksistensi tokoh ini memegang andil besar dalam menjaga harmonisasi dan dinamisasi hubungan antara penduduk asli Minangkabau dengan pendatang dengan cara yang lebih moderat, sistematis dan formal.
B. Saran 1. Secara teoritis, kajian mengenai hubungan hukum adat dengan hukum
Islam di Minangkabau merupakan kajian yang bersifat kompleks dan melibatkan berbagai disiplin ilmu. Diharapkan selanjutnya akan ada kajian khusus antropologi hukum terkait dengan pengaruh kearifan lokal terhadap perkembangan unit pemerintahan terendah di Indonesia.
2. Secara praktis, diperlukan pembahasan lebih lanjut terhadap aspek-aspek genealogis dalam Perda Nagari terkait keanggotaan dan persyaratan bagi tokoh masyarakat yang akan dipilih dan menjabat dalam BAMUS Nagari dan KAN. Diharapkan juga kepada LKAAM untuk mengadakan pendataan ulang terhadap tokoh-tokoh adat yang terdapat dalam masyarakat serta mengadakan serangkaian kegiatan guna meningkatkan SDM para tokoh tersebut. Sebagai sebuah kesatuan sosio-politik yang berlandaskan faktor genealogis, diharapkan pemerintahan nagari melalui ninik melakukan pendataan ulang terhadap suku-suku yang ada dalam nagari dan membuat buku besar yang berisikan ranji keturunan dalam nagari, sehingga nilai-nilai genealogis yang terdapat dalam masyarakat tetap terjaga.
DAFTAR KEPUSTAKAAN BUKU
Abdullah, Rozali. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala
Daerah Secara Langsung. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011. Abdullah, Taufik. Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in
West Sumatera 1927-1933. Ithaca: Cornell Modern Indonesian Project. 1972.
-----------------------. “Modernization in the Minangkabau World: West Sumatera in Early Decades of the 20 Century”. Culture and
Politics in Indonesia, ed. Claire Holt. Itacha and London: Cornell University Press. 1972.
Acciaioli, Gregory L.. “Re-Empowering The Art of Elders: The
Revitalization of Adat Among The To Lindu People of Central Sulawesi and Throughout Contemporary Indonesia”. Beyond
Jakarta: Regional Autonomy and Local Societies in Indonesia. ed. M. Sakai. Adelaide: Crawford House. 2002.
Ahmad Dt. Batuah dan A. Dt. Madjoindo. Tambo Minangkabau dan
Adatnya. Jakarta: Balai Pustaka. 1956. Algar, Hamid. Wahhabism: A Critical Essay. New York: Islamic
Publications International. 2002. Ali, Muhammad Daud. “Hukum Islam: Peradilan Agama dan
Masalahnya”, Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek. ed. Tjun Surjaman. Bandung: Remaja Rosda Karya. 1991.
Arifin, Bustanul. dkk.. Manajemen Suku, eds. Marwan & Bustanul Arifin.
Jakarta: Solok Saiyo Sakato Press. 2012. Asnan, Gusti. Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat Tahun
1950-an. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2007.
246 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
-----------------------, Nagari Pada Masa Kolonial. Padang: Lentera 21. tth. Asnawi. “Pembangunan Sumatera Barat”, Sumatera Barat di Panggung
Sejarah 1945-1995, eds. Mestika Zed, Edy Utama dan Hasril Chaniago. Padang: Bidang Penerbitan Khusus Panitia Peringatan 50 Tahun RI Sumatera Barat. 1995.
Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta:
Konstitusi Press. 2005. -----------------------. Hukum Acara Pengujian Undang-undang. Jakarta:
Sekjend dan Kepaniteraan MK. 2005. ----------------------- dan M. Ali Syafaat. Teori Hans Kelsen tentang
Hukum. Jakarta: Konpress. 2012. Azra, Azyumardi. Surau: Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi
dan Modernisasi. Jakarta: Logos. 2003. -----------------------. Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan
Nusantara Abad XVII & XVIII: Akar Pembaharuan Islam
Indonesia. Jakarta: Kencana. 2013. Baso, Ahmad, Islam Pasca-Kolonial: Perselingkuhan Agama,
Kolonialisme dan Liberalisme. Bandung: Mizan. 2005. -----------------------. “Agar Tidak Memayoritaskan Diri: Tentang Islam,
Pluralisme & HAM Kultural”. Nilai-nilai Pluralisme dalam
Islam: Bingkai Gagasan yang Berserak, ed. Sururin. Bandung: Nuansa. 2005.
Bazemore, G. dan L. Walgrave. “Restorative Community Justice:
Repairing Harm and Transforming Communities”. Understanding
Restorative Community Justice: What and Why Now?. eds. G. Bazemore, et. all.. Cincinnati Oklahoma: Anderson Publishing. 2001.
von Benda-Beckman, Keebet. Goyahnya Tangga Menuju Mufakat.
Jakarta: Grasindo. 2000. ----------------------- and Franz. “Recentralization And Decentralization in
West Sumatera”. Decentralization and Regional Autonomy in
Indonesia: Implementation and Challenges. eds. Coen J.G. Holtzappel dan Martin Ramstedt. Leiden: International Institute for Asian Studies. 2009.
DAFTAR KEPUSTAKAAN | 247
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
-----------------------. “Identitas-identitas Ambivalen: Desentralisasi dan Komunitas-komunitas Politik Minangkabau”. Politik Lokal di
Indonesia. eds. Henk Schulte Nordholt & Gerry van Klinken. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2009.
Benda, Harry J. The Crescent and The Rising Sun. tk: The Hauge. 1958. -----------------------. dkk., Japanese Military Administrasion in Indonesia:
Selected Documents. New Haven: Yale University Southeast Asia Studies. 1965.
Bintarto, R. Interaksi Desa-Kota. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1983. Boland, B. J. The Struggle of Islam in Modern Indonesia. Nijhoff: The
Hauge. 1982. ----------------------- dan I. Farjon. Islam in Indonesia: a Bibliographical
Survey 1600-1942 With Post 1945 Addenda. Dordrcht: Foris Publications. 1983.
Bowen, John R. “Syariah, Negara dan Norma-norma Sosial di Perancis
dan Indonesia”. Dinamika Kontemporer Dalam Masyarakat
Islam, ed. Dick van der Meij. Jakarta: INIS. 2003. Burhanudin, Jajat. Ulama & Kekuasaan: Pergumulan Elite Muslim dalam
Sejarah Indonesia. Bandung: Mizan. 2012. Burke, Peter J. dan Jan E. Stets. Identity Theory. New York: Oxford
University Press. 2009. Burns, Peter, “Adat, Yang Mendahului Semua Hukum”. Adat Dalam
Politik Indonesia. eds. Jamie S. Davidson, David Henley dan Sandra Moniaga. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2010.
Christelow, Allan. Muslim Law Courts and the French Colonial State in
Algeria. New Jersey: Princeton University Press. 1985. Connolly, Peter. “Pendahuluan”. Approaches to the Study of Religion. ed.
Peter Connolly. terj. Imam Khoiri. Yogyakarta: LKiS. 2002. Dallmayr, Fred. “Democracy and Multiculturalism”. Democracy and
Difference: Contesting the Boundaries of the Political. ed. Seyla Benhabib. New Jersey: Princeton University Press. 1996.
248 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Davis, S.H. dan L.T. Soeftestad. “Participation and Indigenous People”
Social Development Paper 9. Washington D.C.: World Bank. 1995.
Deaux, Kay. “Models, Meanings and Motivation”. Social Identity
Processes. eds. Dora Capozza dan Rupert Brown. London: Sage Publications, 2000.
de Jong, P.E. De Josselin. “Minangkabau”. Islam and Society in Southeast
Asia. eds. Taufiq Abdullah & Sharon Siddique. Singapura: Institute of Southeast Studies. 1987.
-----------------------. Minangkabau and Negeri Sembilan: Socio-Political
Structure in Indonesia. Jakarta: Bharatara. 1960. Dias, Thomas, “A Mission to the Minangkabau King”. Witness to
Sumatera: A Traveller’s Anthology. ed. Anthony Reid. Kuala Lumpur: Oxford University Press. 1995.
-----------------------. Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy:
Central Sumatera 1784-1847. London: Curzon Press. 1983. Dwidjowijoto, Riant Nugroho. Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa
Revolusi. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2000. Dwifatma, Andina. Cerita Azra: Biografi Cendikiawan Muslim
Azyumardi Azra. Jakarta: Erlangga. 2011. Edison dan Nasrun, Tambo Minangkabau: Budaya dan Hukum Adat di
Minangkabau. ed. Harry Afrianda. Bukittinggi: Kristal Multimedia. 2010.
Eglash, A.. “Beyond Restitution: Creative Restitution”. Restitution in
Criminal Justice. eds. J. Hudson, et. all.. Lexington Mass: D.C. Health, 1977.
Emirzon, Joni. Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan:
Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2001.
Farouk, Peri Umar. et. all.. Kembali Ke Masa Depan: Otonomi Daerah
Dan Kebangkitan Adat Yang Tidak Pasti. Palangkaraya: Justice for the Poor. 2004.
DAFTAR KEPUSTAKAAN | 249
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Fasseur, C.. “Dilema Zaman Kolonial: van Vollenhoven dan Perseteruan
Antara Hukum Adat dan Hukum Barat di Indonesia”. Adat Dalam
Politik Indonesia. eds. Jamie S. Davidson, David Henley dan Sandra Moniaga. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2010.
Fathurrahman, Oman, Tarekat Syatariyah di Minangkabau. Jakarta:
Prenada Media Group bekerjasama dengan École Française d’Extrême-Orient, PPIM UIN Jakarta dan KITLV. 2008.
Firdaus. “Adat dan Islam: Proses Pembentukan Hukum Islam di
Minangkabau”. Mozaik Islam Nusantara: Seri Agama, Budaya
dan Negara. eds. Nurus Shalihin, et. all.. Padang: Imam Bonjol Press. 2013.
Firmansyah, Nurul. “Eksistensi Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat
Nagari: Catatan Kecil Pengalaman Advokasi di Nagari Kambang, Nagari Guguk Malalo dan Nagari Simanau”. Potret Pengelolaan
Hutan di Nagari. ed. Didin Suryadin. Padang: HuMa. 2007. Galanter, Marc. “Keadilan di Berbagai Ruangan: Lembaga Peradilan,
Penataan Masyarakat serta Hukum Rakyat”. Antropologi Hukum
Sebagai Sebuah Bunga Rampai. Ed. T.O. Ihromi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1993.
Gautama, Sudargo. “Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif (ADR)”.
Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia: Mengenang
Alm. Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, S.H., L.L.M.. ed. Hendarmin Djarab. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2001.
Gazalba, Sidi. Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam. Jakarta:
Pustaka Antara. 1983. Gie, The Liang. Kumpulan Pembahasan Terhadap Undang-undang
Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah di Indonesia. Yogyakarta: Kencana. 1977.
-----------------------. Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara
Republik Indonesia. Yogyakarta: Liberty. 1993. Gonggong, Anhar, “Salah Kaprah Pemahaman Terhadap Sejarah
Indonesia: Persatuan Majapahit dan Piagam Jakarta – Kemayoritasan Islam”. Menjadi Indonesia: 13 Abad Eksistensi
250 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Islam di Bumi Nusantara. eds. Komaruddin Hidayat & Ahmad Gaus A.F. Jakarta: Mizan. 2006.
Graves, Elizabeth E. Asal-usul Elite Minangkabau Modern: Respons
Terhadap Kolonial Belanda Abad XIX-XX. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2007.
Gutman, A. and D. Thompson. Why Deliberative Democracy?. New
Jersey: Princeton University Press. 2004. Guruh, Syahda. Menimbang Otonomi Vs Federal: Mengembangkan
Wacana Federalisme dan Otonomi Luas Menuju Masyarakat
Madani Indonesia. Bandung: Rosda Karya. 2000. Haar, Ter. Hukum Adat dan Polemik Ilmiah. Jakarta: Bharatara. 1973. Hadler, Jeffrey. Sengketa Tiada Putus: Matriarkat, Reformisme Islam dan
Kolonialisme di Minangkabau. Jakarta: Freedom Institute. 2010. Hakimy Dt. Rajo Panghulu, Idrus. Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam
Minangkabau. Bandung: Remaja Rosda Karya. 1994. Hamidi, Jazim dan Kemilau Mutik. Legislative Drafting. Yogyakarta:
Total Media. 2011. Hamka. Ajahku: Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah dan
Perdjuangan Kaum Agama di Sumatera. Jakarta: Djajamurni. 1967.
-----------------------. Islam dan Adat Minangkabau. Jakarta: Pustaka Panjimas. 1984.
Hara, Abubakar Eby. “Pancasila and The Perda Syariah Debates in The
Post-Soeharto Era: Toward A New Political Consensus”. Islam in
Contention: Rethinking Islam and State in Indonesia. eds. Ota Atsushi, Okamoto Masaaki & Ahmad Suaedy. Jakarta: Wahid Institute – CSEAS – CAPAS. 2010.
Harun Dt. Sinaro, Maidir. “Islam dan Budaya Minangkabau”. Menjadi
Indonesia: 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara. eds. Komaruddin Hidayat & Ahmad Gaus A.F. Jakarta: Mizan. 2006.
DAFTAR KEPUSTAKAAN | 251
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Harun, Mohammad. Daerah Otonomi Tingkat Terbawah. Jakarta: Beringin Trading Company. t.th.
Hasan, Iqbal. Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Bogor: Ghalia
Indonesia. 2002. Hazairin. Hukum Kekeluargaan Nasional. Jakarta: Tintamas. 1982. Hitti, Phillip K.. History of The Arabs. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
2006. cet-2. Hodgson, Marshall G. S.. The Venture of Islam: Iman dan Sejarah dalam
Peradaban Dunia. Jakarta: Paramadina. 2002. Holtzappel, Coen J.G. “Introduction: The Regional Governance Reform
in Indonesia, 1999-2004”. Decentralization and Regional
Autonomy in Indonesia: Implementation and Challenges. eds. Coen J.G. Holtzappel dan Martin Ramstedt. Leiden: International Institute for Asian Studies. 2009.
Hornby, A.S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English.
Oxford: Oxford University Press. 1987. Hsiao, Hsin-Huang Michael. “Islam and The State: Teachings and The
Political Reality”. Islam in Contention: Rethinking Islam and State
in Indonesia. eds. Ota Atsushi, Okamoto Masaaki & Ahmad Suaedy. Jakarta: Wahid Institute – CSEAS – CAPAS. 2010.
Huda, Ni’matul. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Rafa Grafindo
Persada. 2005. Hurgronje, Snouck, Islam di Hindia Belanda. Jakarta: Bhratara, 1973. -----------------------. Aceh, Rakyat dan Adat Istiadatnya. Jakarta: INIS.
1996. -----------------------. Islam di Hindia Belanda. Jakarta: Bhratara Karya
Aksara. 1983. -----------------------. Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje IV. eds.
Murni Djamal, dkk. Jakarta: INIS. 1996.
252 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Ibrahim. Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Adat Warisan Nenek
Moyang Orang Minang. ed. Indramaharaja. Bukittinggi: Kristal Multimedia. 2009.
Iglesias, Gabriel U. Regionalization and Regional Development in the
Philiphines. Manila: UP-CPA. 1978. Imawan, Riswandha. “Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan
Good Governance”. Desentralisasi dan Otonomi Daerah:
Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan
Daerah. ed. Syamsuddin Haris. Jakarta: LIPI Press. 2005. Ismatullah, Deddy. “Kata Pengantar”, Otonomi Daerah Dan
Desentralisasi. ed. Utang Rosidin. Bandung: Pustaka Setia. 2010. Jimung, Martin. Politik Lokal dan Pemerintah Daerah Dalam Prespektif
Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pustaka Nusantama. 2005. Julius Dt. Malako nan Putiah. Mambangkik Batang Tarandam Dalam
Upaya Mewariskan dan Melestarikan Adat Minangkabau
Menghadapi Proses Modernisasi Kehidupan Bangsa. Jakarta: Arena Seni. 2007.
Juwaini, Jazuli. Otonomi Sepenuh Hati: Pokok-pokok Pikiran Untuk
Perbaikan Implementasi Otonomi Daerah. Jakarta: al-I’tishom. 2007.
Kahin, Audrey. Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatera Barat dan
Politik Indonesia 1926-1998. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2008.
Kaho, Josef Riwo. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik
Indonesia: Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Jakarta: Raja Grafindo. 2010. Kamil, Sukron. Pemikiran Politik Islam Tematik: Agama dan Negara,
Demokrasi, Civil Society, Syariah dan HAM, Fundamentalisme
dan Antikorupsi. Jakarta: Kencana. 2013. Kansil, C.S.T. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
2008.
DAFTAR KEPUSTAKAAN | 253
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Kartohardikoesoemo, Soetardjo. Desa. Bandung: Sumur. 1953. Kingsbury, B.. “Indigenous People as an International Legal Concept”.
Indigenous People of Asia. eds. R.H. Barnes dan B. Kingsbury. Michigan: Association for Asian Studies. 1995.
van Klinke, Gerry. “Kembalinya Para Sultan: Pentas Gerakan
Komunitarian Dalam Politik Lokal”. Adat dalam Politik
Indonesia. eds. Jamies E. Davidson, et. all.. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2010.
Kurnadi, Moh. dan Bintan R. Saragih. Ilmu Negara. Jakarta: Gaya Media
Pratama. 2007. Legge, J.D. Cultural Authority and Regional Autonomy in Indonesia: a
Study in Local Administration 1950-1960. Ithaca: Cornell University Press. 1961.
-----------------------. Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: Intermasa. 1980.
Lev, Daniel S.. Hukum dan Politik di Indonesia: Kesinambungan dan
Perubahan. Jakarta: LP3ES. 1990. Loeb, Edwin M. Sumatera: It’s History and People. Oxford: Oxford
University Press. 1972. Lubis, M. Solly. Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan
Mengenai Pemerintahan Daerah. Bandung: Alumni. 1974. Lukito, Ratno. Islamic Law and Adat Encounter: the Experience of
Indonesia. Jakarta: INIS. 1998. -----------------------. “Law and Politics in Post-Independence Indonesia: a
Case Study of Religious and Adat Courts”. Shari’a and Politics in
Modern Indonesia. eds. Askal Salim and Azyumardi Azra. Singapore: ISEAS Publishing. 2003.
-----------------------. Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang
Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: Alvabet. 2008.
254 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Maarif, Ahmad Syafii. “Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Indonesia”. Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita. eds. Ahmad Syafii Maarif. et. all.. Jakarta: Democracy Project. 2012.
M, Edison.S., dkk. Tambo Minangkabau: Budaya dan Hukum Adat di
Minangkabau. Bukittinggi: Kristal Multimedia. 2010. M.D., Moh. Mahfud. Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia.
Yogyakarta: UII Press. 2001. -----------------------. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: LP3ES. 1998. Maddick. Democracy, Decentralization and Development. Bombay: Asia
Publishing House. 1963. Madjid, Nurcholis. “Demokrasi dan Demokratisasi”. Demokratisasi
Politik, Ekonomi dan Budaya: Pengalaman Indonesia Masa Orba. ed. Elza Peldi Taher. Jakarta: Paramadina. 1994.
Manan, Bagir. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pusat
Studi Hukum Fakultas Hukum UII. 2002. Manan, Imran. Nagari Pra Kolonial. Padang: Lentera 21. 2003. Mansoer, M. D., dkk. Sedjarah Minangkabau. Jakarta: Bhratara. 1970. Marbun, B.N. Otonomi Daerah 1945-2010: Proses & Realita
Perkembangan Otda Sejak Zaman Kolonial Sampai Saat Ini. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2010.
Mardiasmo. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta:
ANDI. 2004. Marsden, William. The History of Sumatera. London: J. Mc. Creery.
1811. Masrhall, T.. Alternatives to Criminal Courts: The Potential for Non-
Judicial Dispute Resolution. Brookfiled: Gower Publishing Co.. 1985.
DAFTAR KEPUSTAKAAN | 255
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
al Mawardi>. al Ah}ka>m al Sult}a>niyah. Beirut: Da>r al Fikr. t.th. Mawhood, Philip. Local Government in the Third World. Chicester: John
Wisely and Sons. 1983. Merriam, Sharan B. Qualitative Research: a Guide to Design and
Implementation. San Fransisco: John Willey & Sons Inc. 2009. Midgley, James. Pembangunan Sosial: Perspektif Pembangunan Dalam
Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Diperta Islam Depag RI. 2005. Moniaga, Sandra. “Dari Bumiputera Ke Masyarakat Adat: Sebuah
Perjalanan Panjang dan Membingungkan”. Adat dalam Politik
Indonesia. eds. Jamie S. Davison, et.all.. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2010.
Muhadjir, Noeng. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake
Sarasin. 2002. Munir, Ningky Sasanti Tjahyati. “Grounded Theory”, Teori dan
Paradigma Penelitian Sosial: Dari Densin Guba dan
Penerapannya. ed. Agus Salim. Yogyakarta: Tiara Wacana Jogja. 2001.
Muqtafa, M. Khoirul. “Rekonsiliasi Kultural Islam dan Budaya Lokal”.
Nilai-nilai Pluralisme dalam Islam: Bingkai Gagasan yang
Berserak. ed. Sururin. Bandung: Nuansa. 2005. Naim, Mochtar. Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris
Minangkabau. Padang: Centre of Minangkabau Studies. 1968. -----------------------. Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau.
Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1979. -----------------------. “Nagari Versus Desa: Sebuah Kerancuan Struktural”.
Nagari, Desa dan Pembangunan Pedesaan di Sumatera Barat. eds. Mohammad Hasbi, et. all.. Padang: Yayasan Genta Budaya. 1990.
-----------------------. Perspektif Nagari Ke Depan. Padang: Lentera 21. 2003.
256 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Noeh, Zaini Ahmad dan Abdul Basit Adnan. Sejarah Singkat Peradilan
Agama di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu. 1983. Noer, Deliar. The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1980-1942.
London: KI. 1973. -----------------------. The Administration of Islam in Indonesia. Itacha;
Cornell University. 1978. Novitrianti, Dewi. et. all.. Wet Tu Telu: Peluang Membangun Peradilan
di Tingkat Desa. Lombok: Justice fo the Poor. 2004. Parlindungan, M. O. “Kata Sambutan”. Sedjarah Minangkabau. eds. M.
D. Mansoer, dkk. Jakarta: Brathara. 1970. Pires, Tome. The Suma Oriental of Tome Pires, an Account of the East,
From the Red Sea to the Japan, Written in Malacca and India in
1512-1515. ed. Armando Cortesão. New Delhi: Asian Educational Service. 1990.
Poerwadarimta, W.J.S. Pengertian Kesejahteraan Manusia. Bandung:
Mizan. 1996. Rahardjo, Satjipto. Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia. Jakarta:
Kompas. 2003. Ramayulis, dkk. Pemahaman Ninik Mamak Pemangku Adat
Minangkabau Terhadap Nilai-nilai ABS-SBK. Padang: IAIN Imam Bonjol Press. 2009.
Rasyid, Ryaas. “Otonomi Daerah: Latar Belakang dan Masa Depannya”.
Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi,
Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah. ed. Syamsuddin Haris. Jakarta: LIPI Press. 2005.
Reid, Anthony. The Indonesian National Revolution 1945-1950. Connecticut: Greenwood Press. 1974.
Ricklefs, M. C. A History of Modern Indonesia Since c. 1200. Jakarta:
Serambi. 2001.
DAFTAR KEPUSTAKAAN | 257
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Rosidin, Utang. Otonomi Daerah dan Desentralisasi. Bandung: Pustaka Setia. 2010.
Rukmo, J. Endi. “The Role and Function of The Regional People’s
Representative Council (DPRD): A Judicial Study”. Decentralization and Regional Autonomy in Indonesia:
Implementation and Challenges. eds. Coen J.G. Holtzappel & Martin Ramstedt. Leiden: International Institute for Asian Studies. 2009.
Sadjali, Munawir. “Landasan Pemikiran Politik Hukum Islam dalam
Rangka Menantukan Peradilan Agama di Indonesia”. Hukum
Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek. ed. Tjun Suryaman. Bandung: Remaja Rosda Karya. 1991.
Sangaji, Arianto. “Kritik Terhadap Gerakan Masyarakat Adat Indonesia”
Adat dalam Politik Indonesia. eds. Jamie S. Davison, et.all.. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2010.
Saptomo, Ade. Hukum & Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat
Nusantara. Jakarta: Grasindo. 2010. Satriyo, Rudi. et. all.. Advokasi Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga. Jakarta: Balitbang HAM Departemen Kehakiman dan HAM RI. 2006.
Sarundajang. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah. Jakarta: Pustaka
Sinar Harapan. 2000. Siswosoebroto, Koesriani. Pendekatan Baru Dalam Kriminologi. Jakarta:
Universitas Trisakti Press. 2009. Sjarifoedin, Amir. Minangkabau: Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain
Sampai Tuanku Imam Bonjol. Jakarta: Gria Media Prima. 2011. Smith, Brian. Decentralization. London: George Allen and Unwin. 1985. Soehino. Perkembangan Pemerintahan di Daerah. Yogyakarta: Liberty.
1980.
258 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Soekanto, Soerjono. Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia. Jakarta: Kurnia Esa. 1982.
Soemantri, Sri. Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi. Bandung:
Alumni. 2006. Soepomo, R. dan R. Djokosutono. Sejarah Politik Hukum Adat Masa
1848-1928. Jakarta: Prandya Paramita. 1982. Stiglitz, Joseph E. dkk. Mengukur Kesejahteraan: Mengapa Produk
Domestik Bruto Bukan Tolok Ukur Yang Tepat Untuk Menilai
Kemajuan. Jakarta: Marjin Kiri. 2011. Stutterheim, W.F.. De Dateering van Eenige Oost-Javaansche
Beeldengroepen. Batavia: TBG deel LXXVI. 1936. Subekti. Law in Indonesia. Jakarta: Yayasan Proklamasi. 1982. Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung. Alfabeta: 2008. Suharto, Edi. Isu-isu Tematik Pembangunan Sosial: Konsepsi dan
Strategi. Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial. 2004.
Sulastomo. Hari-hari yang Panjang Transisi Orde Lama ke Orde Baru:
Sebuah Memoar. Jakarta: Kompas. 2008. Sulistyo, Adi. Mengembangkan Paradigma Non-Ligitasi di Indonesia.
Surakarta: Sebelas Maret University Press. 2006. Suminto, Aqib. Politik Islam Hindia Belanda. Jakarta: LP3ES. 1986. Supomo dan Djokosutono. Sejarah Politik Hukum Adat 1609-1848.
Jakarta: Djambatan. 1955. Suryadinata, Leo. Penduduk Indonesia: Etnis dan Agama dalam Era
Perubahan Politik. Jakarta: LP3ES. 2003. Swank, Duane. Global Capital, Political Institutions and Policy Change
in Developed Welfare States. New York: Cambridge University Press. 2005.
DAFTAR KEPUSTAKAAN | 259
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Syalabi, A.. Sejarah dan Kebudayaan Islam. Jakarta: Alhusna Zikra. 1995. jilid 2. cet-3.
Syaukani, dkk.. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar. 2003. Thalib, Sajuti. Politik Hukum Baru: Mengenai Kedudukan dan Peranan
Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum
Nasional. Bandung: Bina Cipta. 1987. -----------------------. Receptio A Contrario. Jakarta: Academica. 1980. Toeah, Datoek. Tambo Alam Minangkabau. Bukittinggi: Pustaka
Indonesia. 1976. al-Usairy, Ahmad. Sejarah Islam: Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad
XX. Jakarta: Akbarmedia. 2009. van Vollenhoven, Cristian. Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie.
Leiden: E.J. Brill. 1931. -----------------------. Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia. Jakarta:
Djambatan. 1981. Wahid, Abdurrahman. Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia.
Bandung: Remaja Rosda Karya. 1991. Warman, Kurnia. “Kajian Hukum Tentang Peluang dan Kendala Bagi
Kebijakan Daerah Dalam Penguatan Tenurial Adat”. Potret
Pengelolaan Hutan di Nagari. ed. Didin Suryadin. Padang: HuMa. 2007.
Widjaya, H.A.W. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
Wignjosoebroto, Soetandyo. Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional.
Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1994. -----------------------. Desentralisasi Dalam Tata Pemerintahan Hindia
Belanda. Malang: Bayu Media. 2004. Yandri, Efi. Nagari dalam Prespektif Sejarah. Padang: Lentera 21. 2003. Yogi, A. Rivai. Sastra Minang. Jakarta: Mutiara Sumber Widya. t.th.
260 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Zainuddin, Muhammad. Implementasi Pemerintahan Nagari Berdasarkan
Hak Asal-usul Adat Minangkabau. Yogyakarta: Ombak. 2010. Zulfa, Eva Achjani. Pergeseran Paradigma Pemidanaan. Bandung:
Lubuk Agung. 2011. Zed, Mestika, Eddy Utama dan Hasril Chaniago. Sumatera Barat di
Panggung Sejarah 1945-1995. Padang: Bidang Penerbitan Khusus Panitia Peringatan 50 Tahun Kemerdekaan Indonesia. 1995.
Zehr, Howard. Changing Lenses: A New Focus For Crime and Justice.
Scottsadle Pennsylvania: Herald Press. 1990. -----------------------. The Little Book of Restorative Justice. Intercourse:
Good Books. 2002.
JURNAL & KARYA ILMIAH LAINNYA
Adil, Muhammad. “Simbur Cahaya: Studi Tentang Pergumulan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Kesultanan Palembang Darussalam”. Desertasi SPs UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta: 2009.
Alie, Marzuki. “Kebijakan Desentralisasi Dalam Membangun Kualitas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Era Globalisasi”. Makalah Seminar Nasional Forum Komunikasi dan Kerjasama Mahasiswa Ilmu Pemerintahan se-Indonesia (FOKERMAPI) di Universitas Tadulako Palu Sulawesi Tengah, 06 Oktober 2010.
Andora, Hengki. “Desa Sebagai Unit Pemerintahan Terendah di Kota
Pariaman”. Jurnal Ilmu Hukum. Vol-2, Nomor 1. 2011. Asrinaldi. “Implementasi Demokrasi Lokal di Balik Bayang-bayang
Otonomi Negara”. Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik. Tahun 25. Nomor 2. 2011.
Astuti, Nuraini Budi, dkk. “Dilema Dalam Transformasi Desa Ke Nagari:
Studi Kasus di Kenagarian IV Koto Palembayan Provinsi Sumatera Barat”. Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi,
Komunikasi dan Ekologi Manusia. Vol-3. No. 2. 2009.
DAFTAR KEPUSTAKAAN | 261
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Barnett, R.. “Restitution: A New Paradigm of Criminal Justice”. Ethics
Volume 87. 1977. von Benda-Beckmann, Franz. “Some Comments On The Problems Of
Comparing The Relationship Between Traditional And State Systems Of Administration Of Justice In Africa and Indonesia”. Journal of Legal Pluralism. 12. 1981.
----------------------- and Keebet von Benda-Beckmann. “Recreating The Nagari: Decentralization in West Sumatera”, Working Paper at Max Planck Institute of Social Antrhopology Halle/Yalle. 2001.
von Benda-Beckmann, Keebet. “Development, Law and Gender-
Skewing: An Examination of The Impact of Development on The Socio-Legal Position of Indonesian Women, with Special Reference to Minangkabau”. Journal of Legal Pluralism. 30-31. 1990-1991.
-----------------------. “The Social Significance of Minangkabau State Court Decisions”. Journal of Legal Pluralism. 23. 1985.
Danil, Elwi. “Peluang Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian
Perkara Pidana”. Makalah Musyawarah Adat: Aplikasi Manjemen Suku dan Pemberdayaan Hukum Adat dalam Hukum Nasional. Solok. 23 Maret 2012.
Dobbin, Cristine. “Islamic Revivalism in Minangkabau at the Turn of
Nineteenth Century”. Modern Asian Studies. 8. 1974. Doolin, K.. “But What It Does Mean? Seeking Defenitional Clarity in
Restorative Justice”. Journal of Criminal Law. Volume 71. Nomor 5. 2007.
Dryzek J.S. “Political Inclusion and the Dynamic of Democratization”.
The American Political Science Review. Volume 90. Nomor 3. 1996.
Fatimah, Siti. “Kepemimpinan Tradisional Masyarakat Minangkabau
pada Masa Pendudukan Jepang”. Tingkap Volume VII Nomor 1. 2011.
262 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Fatmariza, “Kesetaraan Gender: Langkah Menuju Demokratisasi Nagari”. Jurnal Demokrasi. Vol-2. Nomor 2114. 2003.
Firdaus. “Konversi Agama dalam Budaya Minangkabau”. Tesis UIN
Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2006. Firmansyah, Nurul. “Peluang dan Tantangan Pengelolaan Sumber Daya
Alam Berbasis Nagari”. Makalah Musyawarah Adat: Aplikasi Majemen Suku dan Pemberdayaan Hukum Adat dalam Hukum Nasional. Solok. 24 Maret 2012.
Furniss N. “The Practical Significance of Decentralization”. The Journal
of Politics. Volume 36. Nomor 3. 1974. Gani, Rita. “Tigo Tungku Sajarangan: Analisis Pola Komunikasi
Kelompok dalam Interaksi Pemimpin Pemerintahan di Sumatera Barat”. Jurnal Mediator. Vol-7. Nomor 2. 2006.
Gavrielides, T.. “Some Meta-Theoretical Questions For Restorative
Justice”. Ratio Juris. Volume 18. Nomor 1. 2005. Indriyanto. “Otonomi dan Pembangunan di Daerah”. Makalah Konfrensi
Nasional Sejarah VII. Jakarta. 28-31 Oktober 2001. Irawati. “Bundo Kanduang dan Tantangan Politik Dalam Badan
Perwakilan Anak Nagari”. Jurnal Demokrasi. Vol-IX. Nomor 1. 2010.
Jaspan, M.A. “In Quest of Law: The Perplexity of Legal Syncretism in
Indonesia”. CSSH. Volume VIII. No 3. 1965. Kamil, Sukron. Demokrasi Dalam Lintasan Sejarah Islam: Dari
Demokrasi Klasik Hingga Kontemporer. Tesis Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta. 1999.
Khatib, Adrianus. “Kaum Paderi dan Gerakan Keagamaan di
Minangkabau”. Disertasi SPs UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 1991.
DAFTAR KEPUSTAKAAN | 263
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Kisworo, Budi. “Relevansi Pemikiran Hazairin tentang Hukum Islam terhadap Proses Pembentukan Hukum Nasional”. Desertasi SPs UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2000.
Kohar, Wakidul. “Komunikasi Antarbudaya di Era Otonomi Daerah”.
Disertasi Doktoral SPs UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2008. Kusumaatmaja, Mochtar. “The Role of Law in Development: The Need
For Reform of Legal Education in Developing Countries”. Role of
Law in Asian Society. Vol II. 1973. Latief, Sanusi. “Gerakan Kaum Tua di Minangkabau”. Jakarta: Disertasi
SPs UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 1987. Lev, Daniel S. “Judicial Unification in Post Colonial Indonesia”.
Indonesia. 16. 1973. Lukito, Ratno. “Hukum dan Politik Pasca-Kemerdekaan Indonesia: Studi
Kasus Agama dan Hukum Adat”. Studia Islamika: Jurnal Kajian
Islam Indonesia. 6. No 3. 1999. McCluskey, G., et. all.. “I was Dead Restorative Today: From Restorative
Justice to Restorative Approach in School”. Cambridge Journal of
Education. Volume 38. Nomor 2. 2008. McCold, P.. “Paradigm Muddle: The Threat to Restorative Justice Posed
by Its Merger With Community Justice”. Contemporary Justice
Review. Volume 7. Nomor 1. 2004. Muntoha. “Otonomi Daerah dan Peraturan-peraturan Daerah Bernuansa
Syariah”. Jurnal Hukum. Volume 15. Nomor 2. 2008. Natin, Sri. “Perubahan Sosial Kedudukan dan Peran Mamak Terhadap
Anak dan Kemenakan di Ranah Minang”. Mimbar Hukum Volume 20 Nomor 2. 2008.
Noer, Melinda. “Pembangunan Berbasis Kelembagaan Adat: Sebuah
Alternatif Pembelajaran Dari Kasus Kinerja Kelembagaan Nagari Dalam Perencanaan Wilayah Di Provinsi Sumatera Barat”. Jurnal
Mimbar. Vol-XXII. Nomor 2. 2006.
264 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Nurdin, Alidinar. “Pentingnya Tanah Ulayat dalam Otonomi Nagari di Propinsi Sumatera Barat”. Makalah Musyawarah Adat: Aplikasi Manajemen Suku dan Pemberdayaan Hukum Adat dalam Hukum Nasional. Solok. 23 Maret 2012.
Okimoto, T.G., et. all.. “Beyond Retribution: Conceptualizing Restorative
Justice and Exploring Its Determinants”. Soc Just Res. 22. 2009. Panggabean, Samsu Rizal. “Federalisasi dan Demokratisasi Indonesia”,
JSP. Volume 1. Nomor 3. 1998. Piliang, Indra J. “Nagari, Demokrasi Lokal dan Good Governance: dalam
Riwayat Muhammad Hatta”. Makalah Temu Nasional Cendikiawan Minang Indonesia dengan tema Sumatera Barat Masa Depan: Sebuah Gagasan Menatap Tatanan baru dalam Bingkai Indonesia. Universitas Gajah Mada Yogyakarta 10-11 Februari 2004.
Popa, Cristin N.. “Restorative Justice: A Critical Analysis”. Law Review.
Volume 2. Nomor 4. 2012. Rafni, Al, et. all.. “Marginalisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat
dalam Pemberdayaan Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat”. Demokrasi Volume VII Nomor 1. 2008.
Raharjo, Trisno. Mediasi Pidana dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat”.
Jurnal Hukum. Volume 17. Nomor 3. 2010. Rahman, Abdul Rasyid. Konsepsi Mohammad Hatta tentang Islam dan
Demokrasi Sosial. Tesis Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta. 1999.
Rahmatunnisa, Mudiayati. “Desentralisasi dan Demokrasi”. Governance.
Volume 1. Nomor 2. Mei 2011. Ramayulis, “Traktat Marapalam Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi
Kitabullah: Diktum Keramat Konsensus Pemuka Adat dan Pemuka Agama Dalam Memadukan Adat dan Islam di Minangkabau Sumatera Barat”. Makalah Annual Conference on
Islamic Studies (ACIS) ke-10 dengan Tema Menampilkan
DAFTAR KEPUSTAKAAN | 265
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Kembali Islam Nusantara, di Banjarmasin Kalimantan Selatan 1-4 November 2010.
Samad, Duski. “Tradisionalisme Islam di Minangkabau: Dinamika,
Perubahan dan Kontinuitasnya”. Tajdid: Jurnal Nasional Ilmu-
ilmu Ushuluddin. vol 6. no 2. 2003. Simon, Gregory Mark. Caged in on the Outside: Identity, Morality and
Self in an Indonesian Islamic Community. Disertasi University of California. San Diego: 2007.
Soemardjan, Selo. “Otonomi Desa Adat”. Jurnal Antropologi Indonesia.
65. 2001. Tamarasari, Desi. “Pendekatan Hukum Adat dalam Menyelesaikan
Konflik Masyarakat pada Daerah Otonom”. Jurnal Kriminologi
Indonesia. Volume 2. Nomor 1. 2002. Thufail, Fadjar I.. “The Social Life of Reconciliation: Religion and The
Struggle for Social Justice in Post-New Order Indonesia”. Working Paper No. 127 Max Planck Institute For Social Anthropology. Halle/Salee. 2010.
Valentina, Tengku Rika, et. all.. “The State Versus Local Elite Conflict in A Transitional Phase of Democracy”. International Journal of
Administrative Science and Organization Vol 18 No 2. 2011. Yunus, Yasril. “Model Pemerintahan Nagari yang Partisipatif dalam
Masyarakat Minangkabau”. Jurnal Demokrasi. Vol-6. Nomor 2. 2007.
Yaswirman. “Hukum Kekeluargaan Adat dan Hukum Kekeluargaan
Islam di Indonesia”. Disertasi SPs UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 1997.
Zevenbergen, J. “System of Land Registration: Aspects and Effects”. PhD
Thesis Technische Universiteit Delf. 2002. Zulfa, Eva Achjani. “Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat
di Indonesia”. Jurnal Kriminologi Indonesia. Volume 6. Nomor 2. 2010.
266 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
WEBSITE Abidin, Mas’ud, Tambo Alam Minangkabau; Penghapusan Sejarah dan
Kekacauan Logika, sebagaimana yang dimuat dalam http://mozaikminang.wordpress.com/2011/11/17/tambo-alam-minangkabau-penghapusan-sejarah-dan-kekacauan-logika/ akses tanggal 27 Desember 2011, 17.21 WIB.
Anggraini, Nelti, Membaca Partisipasi Publik dalam Mendorong
Lahirnya Produk Undang-undang Berdimensi Agama di Sumatra
Barat, dalam http://neltianggraini.blogspot.com/, akses tanggal 23 April 2011, 08:14 WIB.
Annisa, Sulis Syakhsiyah, Perda Wajib Berbusana Muslim di Sijunjung
dalam http://syakhsiyah.wordpress.com/2009/09/18/64/ , akses tanggal 21 April 2011, 15:13 WIB.
Campbell, Beverley, Phenomenology as Research Method (Paper Victoria
University of Technology), sebagaimana yang dimuat dalam http://www.socialresearchmethods.net/kb/qual.php akses tanggal 15 Oktober 2011, 10:22 WIB.
Nadiarlis, Revitalisasi Pendidikan Islam di Sumatera Barat Melalui
Pendidikan Bernuansa Surau, diterbitkan dalam Kompas Online, sebagaimana yang dikutip dari http://ekonomi.kompasiana.com/manajemen/2011/09/12/ revitalisasi-pendidikan-islam-di-sumatera-barat-395140.html akses pada 22 April 2013, 14:09 WIB
Prasojo, Eko, Desentralisasi: Dampak Perubahan Yang Diperlukan,
dalam http://www.forplid.net/modul/134-desentralisasi-dampak-perubahan-yang-diperlukan-.html, akses tanggal 29 September 2011, 12:32 WIB.
Rahardjo, Mudjia, Jenis dan Metode Penelitian Kualitatif. Dalam
http://www.mudjiarahardjo.com/component/content/215.html?task=view, akses tanggal 10 Oktober 2011, 14:09 WIB.
Sudarto, Kesewenang-wenangan Penerapan Hukum Syariah. dalam
http://kiayimassudarto.blogspot.com/2011/04/kesewenang-
DAFTAR KEPUSTAKAAN | 267
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
wenangan-penerapan-hukum. html akses tanggal 18 Oktober 2011, 16:55 WIB.
Suroso, Perda Syariah dalam Sistem Hukum Nasional, dalam
http://fh.wisnuwardhana.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=1 akses tanggal 5 Oktober 2011, 10:33 WIB.
Zubir, Ismail, Religiusitas Masyarakat Minangkabau dan Kebebasan
Beragama/HAM Pasca Undang-undang Otonomi Daerah Nomor
22 Tahun 1999. Dalam http://agama.kompasiana.com/2011/01/21/religiusitas-masyarakat-minangkabau-dan-kebebasan-beragamaham-pasca-uu-otonomi-daerah-no-22-tahun-1999/. Akses tanggal 18 Oktober 2011, pukul 12:09 WIB.
GLOSARIUM acceptable dapat diterima afdeeling satuan administratif pemerintahan
kolonial Belanda alua jo patuik alur dan kepatutan ambtelijke decentralitatie tipikal pemerintahan yang hanya
bersifat dekonsentrasi belaka
angku julukan bagi bagi tetua yang menjadi tokoh adat dan Islam di Minangkabau
clean government pemerintahan yang bersih coffiestelsel tanam paksa kopi darek daerah luhak utama derivatif bersifat tidak langsung
devide et empera politik pecah belah dominion persemakmuran etische politiek politik etis
executoire verklaring ratifikasi putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri (fiat of
execution) floating mass massa mengambang
gemeinschaft masyarakat yang mempunyai hubungan erat dalam komunitasnya, seringkali diidentikkan dengan komunitas masyarakat pedesaan
gewest satuan pemerintahan
good governance pemerintahan yang baik gouverneur-generaal gubernur jenderal gunseikan gubernur militer Jepang gunsireikan pihak militer Jepang
270 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
indigenous peoples masyarakat adat (tribal prople) inlandch politiek kebijakan mengenai penduduk
pribumi dalam usaha memahami dan menguasai pribumi
inyiak julukan kehormatan tokoh Islam di Minangkabau
jorong perkampungan kaba tambo yang diceritakan secara oral korte verklaring kontrak jangka pendek koto himpunan dari beberapa dusun
lange contracten kontrak jangka panjang
lanschaap wilayah di bawah pemerintahan kolonial Belanda
lapau warung larashoofd tuanku lareh lareh federasi nagari-nagari locale verordeningen peraturan setempat medebewind hak untuk menjalankan peraturan
dari pemerintah pusat atau dari daerah yang tingkatnya lebih tinggi berdasarkan perintah
misleading menyesatkan nagari desa adat Sumatera Barat nagari-raad dewan nagari nagarihoofd kepala nagari osamu sierei regulasi yang ditetapkan oleh
kolonial jepang penghulu bajinih penghulu yang diangkat berdasarkan
pilihan masyarakat adat penghulu basurek penghulu yang keanggotaannya
ditunjuk dan disahkan oleh Pemerintah Hindia Belanda
political will keinginan politis point of return titik balik priesterraad pengadilan agama
GLOSARIUM | 271
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
primodial konsanguinal ikatan kedaerahan dan kekerabatan adat
rajo adat raja yang berkuasa dalam bidang adat
rajo ibadat raja yang berkuasa di bidang agama
residentie keresidenan restorative justice upaya penyelesaian sengketa pidana
secara damai di luar pengadilan rigid sifat menunjukkan ketidakmungkinan
mengadakan perubahan
selfbestuur/selfgovernment pemerintahan sendiri selfregelling pengaturan sendiri tambo historiografi tradisional asli milik
masyarakat Minangkabau, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis
taratak daerah hunian para petani yang terpencar, berjauhan dan pada umumnya belum membawa serta istri bersama mereka
tuan kumandua mandor / pengawas uleebalang penghulu adat di Aceh unitary kerangka negara kesatuan vacuum of power kekosongan kekuasaan weltanschauung pandangan hidup (way of life) zelfbestuurende landschappen daerah pemerintahan dalam bentuk
persekutuan asli masyarakat setempat
zelfstandingheid keleluasaan yang besar
SINGKATAN DAN AKRONIM
ABRI Angkatan Bersenjata Republik indonesia ABSSBK Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah AMAN Aliansi Masyarakat Adat Nusantara APB Nagari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari APK Angka Partisipasi Kasar APM Angka Partisipasi Murni APS Angka Partisipasi Sekolah BAMUS Nagari Badan Permusyawaratan Nagari BPD Badan Perwakilan Desa BPH Badan Pengurus Harian BPRD Badan Perwakilan Rayat Daerah BUM Nagari Badan Usaha Milik Nagari BW Burgerlijk Wetboek DAU Dana Alokasi Umum DHN Dewan Harian Nagari DN Dewan Nagari DPAN Dewan Perwakilan Anak Nagari DPD Dewan Perwakilan Daerah DPRD Dewan Perwakilan Raykat Daerah DPRN Dewan Perwakilan Rakyat Nagari GBHN Garis Besar Haluan Negara IGOB Inladsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten ILO International Labour Organization IPM Indeks Pembangunan Manusia IS Indische Staatsregeling KAN Kerapatan Adat Nagari KDH Kepala Daerah Harian KMAN Kongres Masyarakat Adat Nusantara KND Komite Nasional Daerah KNIP Komite Nasional Indonesia Pusat LAN Lembaga Adat Nagari LKAAM Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau MA Madrasah Aliyah MI Madrasa Ibtidaiyah MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat MPRS Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MTKAAM Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau MTs Madrasah Tsanawiyah
274 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia PDRB Produk Domestik Regional Bruto PDRI Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PKKOD Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah PNPM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia RIR Resolutie der Indische Regeering RIS Republik Indonesia Serikat RKPN Rencana Kerja Pembangunan Nagari RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RR Regeering Reglement SDA Sumber Daya Alam SD Sekolah Dasar SMK Sekolah menengah Kejuruan SMP Sekolah Menengah Pertama SMU Sekolah Menengah Umum Stbl Staatsblaad TTS Tigo Tungku Sajarangan VOC Verenidge Oost Indische Compagnie
INDEKS
A
Abdurrahman Wahid 42, 81, 82, 83, 125 ABSSBK 122, 132, 133, 137, 162, 272 Aceh 6, 9, 20, 26, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 45, 47, 54, 60, 82, 83, 86, 124, 131, 251, 271
adat 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 77, 79, 80, 81, 84, 92, 93, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,꩐127, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 175, 177, 178, 179, 180, 182, 212, 221, 225, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 237, 238, 239, 241, 242, 243, 244, 269, 270, 271
Adityawarman 34, 35, 36 Afdeling 141, 142 Agus Salim 55, 255 akulturasi budaya 41, 42, 241 alim ulama 8, 37, 48, 121, 122, 137, 163,
164, 165, 236 alua jo patuik 165, 269 AMAN 124, 125, 272 Amien Rais 81, 85 Azra 7, 8, 15, 16, 28, 38, 39, 48, 121, 138,
246, 248, 253
B
BAMUS Nagari 163, 164, 169, 176, 237, 243, 244, 272
Bank Dunia 119 Budha 29, 32, 33, 35, 43 bundo kanduang 163, 237
C
cadiak pandai 8, 37, 121, 137, 161, 163, 164, 165, 236
coffiestelsel 142, 269 Compendium Freijher 43
D
Daniel S. Lev 64, 66, 67, 68 darek 50, 51, 269 Datuk Katumanggungan 36 Datuk Parpatih Nan Sabatang 36 de Jong 10, 38, 131, 136, 248 demokrasi terpimpin 71, 103, 104, 105, 144 desentralisasi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 16,
17, 18, 19, 21, 23, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 107, 109, 110, 120, 121, 123, 125, 126, 148, 149, 151, 242, 266
devide et empera 46, 269 Dinasti T’ang 30, 31 Djamil Djambek 56, 62
E
efektivitas 18, 19, 23, 84, 151, 160, 171, 173, 225
ekspedisi pamalayu 32 Elizabeth E. Graves 26, 28, 38, 50, 54, 136,
137 etische politiek 91, 269 executoire verklaring 76, 77, 269
F
formalisasi 117, 133, 155, 243
G
Gajah Mada 16, 34, 255, 264 Golkar 81, 167 good governance 16, 17, 150, 269 Gyu Gun 62, 63
H
Habibie 82, 83, 125 HAM 6, 9, 10, 20, 80, 81, 117, 118, 119,
122, 234, 235, 246, 252, 257, 267 Hamka 32, 39, 49, 55, 152, 250
276 │AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Hanbali 48, 51 Hatta 16, 60, 63, 66, 126, 127, 128, 264 Hayam Wuruk 34 Hazairin 46, 65, 72, 76, 154, 251, 262 Hindu 9, 34, 35, 37, 45 hukum adat 6, 7, 12, 13, 15, 18, 25, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 67, 68, 69, 70, 74, 79, 93, 117, 123, 129, 130, 138, 146, 150, 151, 154, 155, 158, 166, 167, 169, 170, 172, 173, 177, 212, 225, 229, 230, 234, 235, 238, 239, 241, 242
hukum Islam 6, 13, 15, 17, 18, 25, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 55, 60, 63, 66, 67, 68, 69, 74, 76, 77, 79, 242, 244
I
identitas 5, 14, 17, 59, 79, 80, 82, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 129, 131, 135, 138, 143, 153, 154, 165, 170, 234, 247
ideologi 9, 32, 50, 52, 59, 71, 76, 77, 80, 123 IGOB 130, 131, 141, 178, 272 ILO 119, 272 Imam Bonjol 9, 26, 37, 53, 139, 249, 256,
257 indigenous people 119 inlandch politiek 45, 269 Inyiak 56 IPM 23, 216, 220, 221, 222, 223, 224, 225,
226, 272
J
jorong 73, 145, 157, 163, 178, 180, 183, 184, 269
K
kaba 27, 270 KAN 146, 147, 148, 161, 164, 165, 167,
168, 169, 170, 172, 175, 176, 182, 225, 234, 235, 236, 237, 239, 243, 244, 272
kearifan lokal 6, 58, 86, 151, 242, 244 kejahatan 15, 68, 228, 229, 230, 231, 232,
234 KNIP 96, 272 kolonialisme 15, 25, 45, 53, 58, 75, 89, 177,
241 konflik 6, 8, 11, 15, 24, 31, 39, 45, 47, 51,
64, 68, 69, 73, 74, 125, 166, 227, 229, 230, 232, 233, 237, 244
korban 15, 166, 228, 230, 232 korte verklaring 93, 270 Koto 36, 138, 156, 177, 260 Kubilai Khan 33, 34
L
Landraad 44 lange contracten 93, 270 living law 19, 68 LKAAM 165, 167, 168, 244, 272 Luhak 49, 50, 55, 141
M
Majapahit 34, 35, 66, 249 Maklumat 95, 143, 144, 174, 234 Max Webber 72 medebewind 93, 97, 100, 270 Megawati 82, 83 Minangkabau 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
16, 17, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 65, 73, 79, 80, 81, 92, 117, 120, 121, 122, 123, 124, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 171, 172, 173, 177, 178, 179, 212, 221, 225, 227, 230, 232, 233, 234, 235, 238, 239, 241, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 250, 252, 254, 255, 256, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 269, 270, 272
Mochtar Naim 36, 47, 132, 137, 140, 148, 162, 179
Muawiyyah 31
N
nagari 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 20, 23, 32, 35, 37, 38, 39, 41, 48, 54, 73, 80, 81, 92, 99, 117, 120, 121, 123, 127, 128, 129, 130, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184,
INDEKS│277
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
186, 188, 189, 208, 209, 211, 212, 221, 223, 225, 226, 227, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 270
ninik mamak 8, 121, 122, 137, 144, 158, 162, 163, 164, 165, 167, 170, 172, 227, 236, 240
O
Orde Baru 6, 8, 15, 70, 71, 72, 73, 81, 107, 120, 121, 124, 125, 130, 132, 145, 165, 167, 189, 258
otonomi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 68, 69, 72, 79, 80, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 120, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 140, 141, 143,꩐147, 148, 149, 151, 152, 153, 160, 161, 162, 164, 178, 182, 235, 236, 237, 240, 242, 267
P
Paderi 10, 15, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 122, 140, 262
Pagaruyung 32, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 52, 136
Pancasila 70, 71, 122, 250 pemekaran 23, 80, 114, 165, 177, 179, 184,
186, 187, 189, 208, 212, 223, 226, 243 pemulihan 83, 161, 173, 228, 229 Penghulu 37, 50, 52, 55, 66, 141, 142, 156,
159, 172 Perda 1, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 16, 22, 23, 122,
129, 133, 146, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 163, 164, 165, 172, 173, 175, 176, 179, 182, 184, 190, 225, 236, 238, 239, 244, 250, 266
Plakat Panjang 53, 140, 142, 178 politik 1, 5, 6, 11, 14, 18, 20, 23, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 60, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 86, 89, 90, 91, 93, 95, 98, 102, 106, 107, 110, 111, 112, 114, 117, 118, 119, 122, 123, 124, 125, 130, 131, 135, 136, 137, 140, 142, 145, 148, 153, 167, 169, 189, 212, 216, 226, 232, 234, 236, 237, 238, 239, 241, 244, 269
Pristerraad 44
pusako 155, 158, 165, 176, 236, 239
R
rajo adat 38 rajo ibadat 38, 270 rantau 28, 29, 40, 50, 140, 151, 170, 177 Ratno Lukito 6, 15, 44, 47, 57, 58, 59, 60,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 74, 75 receptie 12, 43, 45, 46, 65 receptie a contrario 12, 66 receptie exit 12, 66 Reformasi 1, 65, 109, 174 restorative justice 146, 162, 166, 227, 228,
229, 230, 231, 232, 233, 270
S
sako 158, 165, 176, 236, 239 Sha>fii 42, 49, 51, 54 Shekh Abdurrauf Singkil 36 Shekh Ah}ma>d Kha>tib al Minangkabawi 55 Shekh Burhanuddin 36, 40 Shiah 49 Sjahrir 60 Snouck Hurgronje 9, 44, 45, 55, 129, 131,
251 Soeharto 1, 70, 71, 76, 81, 82, 83, 108, 122,
123, 125, 130, 167, 250 Soekarno 60, 63, 66, 71, 76, 82, 83, 103 Soepomo 64, 75, 130, 131, 258 Sriwijaya 30, 31, 32, 35 Staatsblaad 43, 46, 90, 91, 92, 100, 273 suku 3, 7, 25, 26, 48, 55, 59, 86, 87, 135,
139, 140, 147, 149, 152, 156, 158, 159, 161, 162, 168, 171, 182, 234, 238, 244
Sultan Alaudin Riayatshah al Qahha>r 39 Sultan Alif 37, 38 surau 7, 12, 16, 48, 56, 123, 132, 133, 147,
168, 175 Susilo Bambang Yudhoyono 83
T
tali tigo sapilinan 37, 164 tambo 26, 27, 28, 32, 36, 139, 265, 270 taratak 138, 139, 155, 271 Ter Haar 46, 47, 131 tribal people 119 tungku nan tigo sajarangan 37 Turki Utsmani 51
278 │AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
U
ulayat 6, 70, 117, 138, 139, 153, 157, 168, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 212
uleebalang 45, 60, 271 Umar ibn Abd Azi>z 31 Umayyah 30, 31 Undang-undang 1, 2, 5, 6, 10, 18, 19, 20, 35,
68, 70, 73, 75, 76, 77, 84, 85, 87, 89, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 120, 125, 127, 128, 133, 145, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 179, 180, 182, 215, 231, 234, 246, 249, 266, 267
unifikasi 64, 67, 68, 69, 72, 74, 129, 130, 146, 147, 183, 229, 234, 242
V
van den Berg 43, 44, 45, 226 van Vollenhoeven 44, 46, 47, 67, 74, 130,
131, 226 vis a vis 48, 69 VOC 43, 47, 273 von Benda-Beckmann 1, 14, 122, 129, 131,
135, 143, 145, 146, 148, 154, 157, 163, 165, 166, 170, 234, 261
W
Wahabi 48, 49, 50, 51
Z
zelfbestuurende landschappen 92, 153, 271 zelfstandingheid 133, 271
DAFTAR RIWAYAT
HIDUP Nama : Aulia Rahmat, S.H.I., M.A.Hk. Tempat Tanggal Lahir
: Solok, 8 Januari 1987
Alamat : Jalan Raya Bintara Jaya Nomor 23A RT/RW 002/009 Kelurahan Bintara Jaya Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi – Jawa Barat 17136
Contact Person : +6281363759020 / +6282111137545
A. Orang Tua
1. Ayah Nama : Drs. Ahmad Saiyadi Syarif Tempat Tanggal Lahir : Pantai Cermin, 2 Januari 1958 Alamat : Jl. K.H. Fachruddin Saleh Nomor 75
Jorong Balai Pinang Nagari Muaropaneh Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok – Sumatera Barat 23178
2. Ibu Nama : Dra. Hasnetti Tempat Tanggal Lahir : Muaropaneh, 25 Juni 1958 Alamat : Jl. K.H. Fachruddin Saleh Nomor 75
Jorong Balai Pinang Nagari
280 | AULIA RAHMAT
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
Muaropaneh Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok – Sumatera Barat 27381
B. Riwayat Pendidikan
1. Taman Kanak-kanak (TK) Aisiyah 1 Balai Gadang Nagari Muaro
Paneh, Kecamatan Bukit, Sundi Kabupaten Solok (1992-1993, berijazah);
2. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 10 Koto Panjang, Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Sumatera Barat (1993-1999, berijazah);
3. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Pesantren Modern Terpadu (SLTP PMT) Prof. Dr. Hamka Pasar Usang, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat (1999-2002, berijazah);
4. Madrasan Aliyah Negeri (MAN) 2 Kotobaru Kabupaten Solok, Sumatera Barat (2002-2005, berijazah);
5. Jurusan Ahwal al Shakhshiyyah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat (2005-2009, berijazah);
6. Program Studi Syariah, Konsentrasi Pengkajian Islam, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (SPs UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (2010-sekarang).
C. Riwayat Organisasi
1. Ketua I Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) MAN 2 Kotobaru
Kabupaten Solok (2002-2003); 2. Ketua Umum Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) MAN 2
Kotobaru Kabupaten Solok (2003-2004); 3. Pengurus Harian Majalah Dinding “Al-Bayan”, Himpunan
Mahasiswa Jurusan Ahwal al Syakhshiyyah, Fakultas Syariah, IAIN Imam Bonjol Padang (2005-2006);
4. Anggota Komisi B (Bidang Advokasi) Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Syariah (DPM-FS) IAIN Imam Bonjol Padang (2006-2008);
DAFTAR RIWAYAT HIDUP |281
REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH
5. Sekretaris Umum Senat Mahasiswa Fakultas Syariah (SMF Syariah) IAIN Imam Bonjol Padang (2008-2009);
6. Sekretaris Umum Dewan Perwakilan Provinsi Forum Mahasiswa Syariah se-Indonesia (DPP Formasi) Sumatera Barat (2008-2009);
7. Peneliti Muda Revault Institute Padang (2009-2010); 8. Anggota Bidang Kepemudaan dan Olahraga Ikatan Keluarga
Perantau Muaropaneh (IKPM) Jabodetabek (2010-2012); 9. Sekretaris Umum Ikatan Keluarga Perantau Muaropaneh (IKPM)
Pusat (2012-2014).
D. Karya Tulis 1. Relevansi Antara Khitan Perempuan dan Female Genital
Mutilation (FGM) di Indonesia (Jurnal Rihlah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Attahiriyyah Jakarta: Volume I, Nomor 1, Januari-Juni 2011, ISSN 2252-7478);
2. Status Hukum Anak Angkat Dalam Hukum Keluarga Kontemporer Negara Muslim: Analisis Komparatif Vertikal, Horizontal dan Diagonal serta Pengaruh Sosio-Historis (Jurnal Al-Sakinah Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang: Volume VII, Nomor 1, 2012, ISSN 1410-4687).