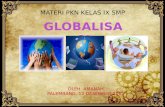“Studi SoSiologi Militer dalaM KonteKS globaliSaSi dan ...
Transcript of “Studi SoSiologi Militer dalaM KonteKS globaliSaSi dan ...

“Studi SoSiologi Militer dalaM KonteKS globaliSaSi
dan KontribuSinya bagi tranSforMaSi tni”
AMARULLA OCTAVIAN
Cetakan Kedua
bab1-2 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 1 7/10/12 1:55 PM

2
Menuju masyarakat
dengan militer
unggulan
bab1-2 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 2 7/10/12 1:55 PM

3
bab1-2 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 3 7/10/12 1:55 PM

4
Cetakan Kedua 2012
Penerbit: UI Press-Jakarta
Pemilik Hak Cipta: Amarulla Octavian
Naskah: Amarulla Octavian
Penyunting: Deniek G. Sukarya
Direktur Kreatif: Taja Sukarya
Desain Grafis: PT Sukarya & Sukarya Pandetama
Dicetak di Jakarta, Indonesia 2012
ISBN 978-979-456-475-2
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Tidak ada bagian dari buku ini yang boleh direproduksi dalam bentuk apapun atau dengan cara elektronik ataupun cara mekanik, termasuk dalam sistem penyimpanan informasi dan kearsipan, tanpa ijin tertulis dari penerbit dan atau pemilik Hak Cipta kecuali oleh pengulas yang diperbolehkan mengambil kutipan pendek dalam ulasannya.
bab1-2 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 4 7/10/12 1:55 PM

5
Kata Sambutan dari Prof. Dr. Purnomo Yusgiantoro ..........................................................6Kata Pengantar dari Dr. Iwan Gardono Sujatmiko .............................................................8Prakata Penulis ....................................................................................................................12Bab I. Pendahuluan ..............................................................................................................161.1. Globalisasi dan Persoalan Keamanan ..............................................................................171.2. Sosiologi Militer .............................................................................................................20Bab II. Diskursus Globalisasi dalam Kajian Militer ..........................................................262.1. Pandangan Globalisasi Anthony Giddens dan Kajian Sosiologi Militer ...........................262.2. Gagasan Regionalisme Ekonomi Kenichi Ohmae ............................................................312.3. Keith Faulks: Mengembalikan Negara ............................................................................342.4. Jonathan Krishner dan Persoalan National Security ........................................................372.5. Studi Empirik Norin Ripsman dan T.V. Paul ...................................................................402.6. Rangkuman .....................................................................................................................48Bab III. Globalisasi dan Revolutionary in Military Affairs .................................................543.1. Globalisasi dan Keamanan Nasional ...............................................................................543.2. Perkembangan Pemikiran Revolutionary in Military Affairs ............................................573.3. Belanja Teknologi Militer Dunia .....................................................................................623.4. Globalisasi dan Konflik Antar Negara .............................................................................693.5. Transnational Organized Crimes .....................................................................................753.6. Rangkuman .....................................................................................................................80Bab IV. Transformasi Militer - Studi Beberapa Negara.....................................................864.1. Perubahan Paradigma Peperangan ...................................................................................864.2. Praktik Transformasi Militer di Eropa .............................................................................894.3. Pengalaman Transformasi Militer di Asia ........................................................................924.4. Perbandingan Kasus Transformasi Militer Cina dan Amerika Serikat ............................1014.5. Rangkuman ................................................................................................................... 112Bab V. Militer Indonesia dan Pemetaan Kebijakan ......................................................... 1185.1. Reorganisasi dan Rasionalisasi Militer Indonesia dari Masa Ke Masa ........................... 1195.2. Pengaruh Dinamika Lingkungan Global terhadap Militer Indonesia..............................1355.3. Dampak Jangka Panjang Perkembangan Militer Indonesia ............................................1445.4. Rangkuman ...................................................................................................................146Bab VI. Skenario Awal Transformasi TNI ........................................................................ 1546.1. Mengapa Perlu Transformasi? .......................................................................................1546.2. Skenario Tingkat Global ................................................................................................1576.3. Skenario Tingkat Nasional ............................................................................................1626.4. Rangkuman ...................................................................................................................167Bab VII. Kontribusi Teoritik Studi Militer .......................................................................172 7.1. Ikhtiar Mencari Paradigma Globalisasi Khas Indonesia ................................................1727.2. Melihat Militer dari Perspektif Sosiologik ....................................................................1747.3. Kontribusi Pemikiran Globalisasi dalam Khasanah Sosiologi Militer ............................1767.4. Cairnya Tembok Sipil-Militer: Kritik atas Huntington ..................................................1787.5. Masa Depan Ranah Kajian Sosiologi Militer .................................................................1847.6. Rangkuman ...................................................................................................................186Bab VIII. Penutup ..............................................................................................................190Daftar Pustaka ......................................................................................................................192Indeks ..................................................................................................................................197
Daftar Isi:
bab1-2 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 5 7/10/12 1:55 PM

6
Memasuki abad kedua puluh satu, paradigma sistem pertahanan negara mengalami pergeseran. Landasan ideologis pertahanan negara bangsa (nation state) seperti Indonesia perlu semakin disinergikan dengan kekuatan ekonomi, teknologi, dan informasi. Kekuatan segi tigapenentu merupakan kekuatan dunia pada abad kedua puluh satu ini. Ahli sosiologi, Profesor Dr. Manuel Castells (2010) dalam bukunya The Power of ldentity. The Information Age: Economy, Society, and Culture, mengemukakan bahwa penguasaan atas kekuatan segi tiga dapat melampaui
kekuatan konvensional karena berbasis pada kekuatan jaringan, dan tidak lagi semata-mata mengandalkan kemampuan internal suatu bangsa. Menurutnya, kekuasaan jaringan aktor elite mampu melintasi batas-batas wilayah, etnik, agama, kebudayaan, dan bahkan negara. Jaringan ini mampu mempengaruhi dan mendorong negara mengikuti kehendak jaringan tersebut. Akankah negara bangsa lenyap dan digantikan oleh suatu bentuk kekuasaan baru yang disebut masyarakat jaringan (network society) yang memiliki ciri-ciri lintas batas?
Tidak semua negara bangsa seperti lndonesia akan kehilangan kekuasaannya. Banyak negara bangsa yang tetap kuat hingga abad ini, salah satunya adalah Amerika Serikat. Selain itu ada sejumlah negara bangsa mengambil jalan tengah, membentuk jaringan negara seperti Uni Eropa. Sumber kuncinya pada kekuatan dan kekuasaan ekonomi, teknologi, dan informasi suatu bangsa. Bagi suatu negara bangsa yang lemah dalam ketiga kekuatan itu posisinya bisa tergeser dalam percaturan internasional. Banyak negara yang semakin tergantung pada masyarakat jaringan lintas batas, bahkan untuk mengambil keputusan ekonomi di dalam negeri sendiri.
Mengingat negara kita adalah negara bangsa yang majemuk, maka sistempertahanan negara secara konvensional disesuaikan dengan ciri kemajemukandalam kondisi geografis kepulauan yang sangat luas itu. Pada masa lalu,kebijakan politik nasional kita dibangun dan dijalankan bersifat sentralistis, dan ideologi negara menjadi basis sentral untuk mendorong dan membangkitkan kesadaran akan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air. Perubahan dunia telah
Kata Sambutan Menteri Pertahanan Republik IndonesiaProf. Dr. Purnomo Yusgiantoro
bab1-2 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 6 7/10/12 1:55 PM

7
mendorong kita untuk melakukan penyesuaian yang relevan dengan era ekonomi, teknologi dan informasi. ldeologi negara dan kesejahteraan rakyat ibarat dua sisi koin yang tak terpisahkan. Kesejahteraan rakyat adalah kata kunci kesuksesan pertahanan negara masa kini. Secara bertahap tapi pasti, Kementerian Pertahanan sebagai penjuru pertahanan nasional mulai melangkah memasuki paradigma baru, yakni ke arah pembangunan Sistem Pertahanan Negara yang pro kesejahteraan, yang senafas dengan demokrasi.
Pergeseran paradigma global tersebut membawa dampak terhadap fungsi dan peranan militer. Kebijakan pertahanan negara kita memiliki dua dimensi yang merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan, yakni pertahanan militer dan pertahanan nir militer. Fungsi dan peranan militer pun terdiri dari dua dimensi yakni fungsi dan peranan militer untuk perang, dan fungsi dan peranan militer selain perang, disebut Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Tatkala ancaman tradisional dengan mengerahkan pasukan dan persenjataan lengkap mungkin jarang lagi terjadi, ancaman yang timbul akibat globalisasi akan sering hadir dan cenderung meningkat. Dalam hal ini militer kita mengemban fungsi dan peranan militer selain perang yang penting, khususnya dalam menangani antara lain cyber war, terorisme, pembajakan, bencana alam, dan ikut serta secara aktif dalam misi pemeliharaan perdamaian di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa.
Berdasarkan hal di atas, saya menyambut baik dan mengucapkan selamat atas terbitnya buku Saudara Amarulla Octavian, seorang perwira TNI Angkatan Laut, yang membahas topik sosiologi militer dalam konteks globalisasi dan kontribusinya bagi transformasi TNl. Buku ini salah satu dari masih sedikitnya karya para anggota TNI yang membahas fungsi dan peranan militer dalam era yang selalu berubah. Suatu pembahasan tentang state of the art mengenai fungsi dan peranan militer dari waktu ke waktu yang sangat penting, perlu dan selalu menarik. Khususnya yang ditulis oleh para perwira TNI kita sendiri.
Jakarta, 27 Maret 2012
Kata Sambutan Menteri Pertahanan Republik IndonesiaProf. Dr. Purnomo Yusgiantoro
Purnomo Yusgiantoro
bab1-2 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 7 7/10/12 1:55 PM

8
Beragam Globalisasi
Globalisasi merupakan suatu fenomena yang semakin populer saat ini dan ditandai dengan kemajuan teknologi sehingga ada yang menyebutnya sebagai “kematian jarak” (death of distance). Dengan teknologi komunikasi informasi, peristiwa di tempat yang jauh dapat diketahui saat itu juga (real time) dan simultan di berbagai tempat. Globalisasi juga sering disinonimkan dengan westernisasi karena gaya hidup yang semakin sama seperti Barat (Eropa dan Amerika Serikat), misalnya mengglobalnya McDonald atau musik pop yang dapat menembus negara (bekas) Tirai Besi dan Tirai Bambu. Demikian juga globalisasi ditandai dengan adanya jaringan internet (WWW) dan Facebook yang anggotanya mencapai hampir satu miliar orang (“netizen”), yang jumlahnya hanya kalah oleh penduduk Cina dan India.
Namun sebenarnya globalisasi mempunyai sejarah yang lebih panjang dan mencakup banyak aspek dalam masyarakat. Dalam hal ini globalisasi merupakan proses perubahan dari sesuatu yang lokal menjadi ke skala global atau dunia. Sebagai contoh, jutaan tahun yang lalu telah dimulai globalisasi manusia yang berasal dari Afrika (“out of Africa”) yang menyebar ke berbagai belahan dunia. Demikian juga dilihat dari teknologi, telah mulai mengglobal semenjak Revolusi Agraris sekitar 10.000 tahun lalu dari daerah Bulan Sabit yang subur (“Fertile Crescent”) di sekitar Mesopotamia, yang mencakup daerah-daerah di Suriah, Lebanon, Palestina, Jordania, Israel, Irak, Iran, dan Turki. Revolusi Agraris ini diikuti oleh Revolusi Industri yang dimulai di Inggris dan juga Revolusi Informasi di Amerika Serikat dua dekade terakhir. Sejalan dengan ini terjadi pula globalisasi kapitalisme, baik pencarian sumber alam maupun pasar, yang erat dengan kolonialisme, yang berhubungan dengan imperialisme di mana penguasaan ekonomi menjadi dan saling mendukung dengan penguasaan politik.
Jika dilihat dari aspek budaya, maka globalisasi masa kini terkait dengan penyebaran peradaban yakni Hindu-Budhisme; Kristen; Islam; dan Cina. Proses ini dilengkapi dengan ideologi yang berasal dari Barat (Eropa) seperti kapitalisme, sosialisme, komunisme, nasionalisme, dan demokrasi. Dalam sejarahnya, Indonesia dan pra-
Kata Pengantar Sosiolog, FISIP-UI Dr. Iwan Gardono Sujatmiko
bab1-2 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 8 7/10/12 1:55 PM

9
Indonesia mengalami proses yang kompleks, seperti adanya persilangan budaya yang terjadi di Jawa sebagaimana dibahas dalam buku Denys Lombard (Nusa Jawa: Silang Budaya, Jilid I, II, III, 2005). Jawa dan Nusantara mengalami proses silang budaya atau globalisasi (peradaban) Eropa (Kristen), Cina, India (Hindu-Budhisme), dan Arab (Islam) yang mempengaruhi kelompok dan budaya lokal, yang terpaksa menyesuaikan dengan kekuatan global ini. Silang budaya ini kemudian juga diikuti oleh persaingan dan konflik antara agama (Islam), nasionalisme, dan komunisme sejak awal abad ini dan mencapai puncaknya pada tahun 1965 di mana terjadi polarisasi antara ”Nas” dan ”A” melawan ”Kom”, yang berakhir dengan kehancuran ”Kom.” Setelah peristiwa itu terjadi proses kerjasama dan juga konflik antara nasionalisme dan agama (Islam) dalam berbagai aspek kemasyarakatan. Proses ini mencakup juga kelompok agama minoritas (Kristen dan Hindu Bali) serta budaya lokal (adat), seperti yang berada di Papua dan Kalimantan. Konflik, Kerjasama, Kompetisi
Dilihat dari aspek sosiologi, maka globalisasi seperti yang dibahas di atas dapat diartikan sebagai “suatu proses di mana beragam hubungan sosial berupa konflik, kerjasama, dan kompetisi yang berkaitan dengan sumber daya dan identitas menjadi semakin intensif dan ekstensif dalam dunia yang semakin menyatu”. Dalam hal ini, globalisasi militer merupakan proses di mana arena persaingan dan konflik antar negara menjadi semakin menyempit sehingga satu konflik atau perang dapat mencakup hampir seluruh wilayah bumi seperti Perang Dunia Kesatu dan Kedua. Namun dalam realitanya, ketiga proses tersebut dapat saling terkait sehingga konflik dapat saja berisi aspek kerjasama juga. Sebagai contoh, di era Perang Dingin, dua ”super power” (Amerika Serikat dan Uni Sovyet) yang berkonflik ini melakukan kompetisi persenjataan, namun mereka juga bekerjasama erat (termasuk melalui ”hot line”) untuk mencegah konflik yang dapat memusnahkan keduanya (“MAD” atau “Mutual Assured Destruction”).
Dalam dunia yang semakin kompleks karena globalisasi dalam aspek ekonomi dan budaya, maka konflik militer (perang) bukan hanya terkait dengan perebutan teritorial. Perang sejak awalnya dapat terjadi karena faktor politik (perebutan wilayah), ekonomi (sumber daya) atau simbol. Dalam hal ini terjadi keterkaitan antara konflik dengan kompetisi sumber daya alam seperti yang sering dianggap sebagai penyebab perang
bab1-2 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 9 7/10/12 1:55 PM

10
di Timur Tengah. Tidaklah salah terdapat anggapan bahwa perang dan militer dapat juga berfungsi sebagai kepanjangan dari perusahaan besar (TNC) dalam proses utama mereka, yakni peningkatan laba yang tiada henti.
Di era globalisasi ini militer dituntut pula untuk berkontribusi dalam bidang non militer, seperti ekonomi. Misalnya, militer Cina dan Malaysia yang bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB (U.N. Peacekeeping Force) membantu membangun jaringan bisnis di Afrika. Demikian juga beberapa negara mendukung anggota militer untuk berkompetisi dan berprestasi dalam olahraga internasional sehingga akan mengharumkan nama negaranya. Selain mempunyai fungsi utama sebagai “pagar” pertahanan negara dan siap berkonflik (perang), militer juga terlibat dalam proses kompetisi dan kerjasama. Salah satu bentuk kerjasama diperlihatkan dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) di mana mereka bekerjasama dengan kelompok-kelompok lain yang ada di negara mereka dalam mengatasi masalah sosial dan melaksanakan pembangunan negara bangsa. Demikian pula, militer melakukan kompetisi untuk menunjukkan siapa yang lebih unggul atau profesional dalam latihan atau kerjasama dengan militer negara lain. Secara singkat dapat dikatakan bahwa militer setiap negara—sebagai suatu organisasi—dituntut untuk unggul dalam berkonflik, berkompetisi dan bekerjasama.
Berkaitan dengan hal ini, menarik untuk mengevaluasi sejauh mana strategi berkonflik, berkompetisi, dan bekerjasama yang dilaksanakan tersebut memang benar-benar unggul. Apakah militer suatu negara termasuk unit-unitnya selalu meningkatkan kemampuan mereka secara terus menerus dengan melakukan riset, pilot project, atau kerjasama internasional ? Apakah Penelitian dan Pengembangan (Litbang) dalam militer lebih merupakan proses rutin dan birokratis atau memfokuskan pada terobosan-terobosan untuk peningkatan kemampuan ? Apakah indikator yang ada dapat memposisikan sejauh mana militer dalam setiap tahun telah lebih sukses dalam berkonflik, berkompetisi, dan bekerjasama ? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu diketahui dan dijawab serta ditindak-lanjuti oleh transformasi militer di Indonesia (TNI) sehingga mereka lebih siap dalam menghadapi globalisasi.
Dari Indonesia untuk Dunia
Globalisasi merupakan proses dua arah di mana berbagai aktor (negara maupun non negara) telah memasuki dan mempengaruhi Indonesia atau “globalisasi dari luar”.
bab1-2 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 10 7/10/12 1:55 PM

11
Namun, keadaan sebaliknya juga telah terjadi di mana Indonesia dapat berkontribusi pada dunia atau “globalisasi dari kita/dalam”. Sebagai contoh, Indonesia telah secara aktif mengirim Kontingen Garuda sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB. Selain itu pendirian Indonesia Peace and Security Center (IPSC) di Sentul, Bogor mempunyai potensi untuk menjadi pusat kegiatan militer dari berbagai negara serta PBB, dan berperan positif di era globalisasi. Demikian juga pemikiran Jenderal A.H. Nasution yang berupa buku “Pokok-Pokok Perang Gerilya” (1953) telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa dan berpengaruh pada beberapa negara serta forum global. Kasus lain ditunjukkan oleh kapal TNI AL “KRI Dewaruci” yang telah melanglang buana atau mengglobal untuk menunjukkan semangat dan tradisi kebaharian. Hal ini merupakan suatu kegiatan positif yang tidak dilakukan oleh banyak negara walaupun mereka lebih mampu secara ekonomi dan teknologi. Berbagai contoh ini menunjukkan bahwa kontribusi Indonesia untuk dunia dapat dilakukan meskipun kekuatan dan kekayaan Indonesia relatif terbatas. Kegiatan positif ini dapat dan perlu lebih ditingkatkan dengan membuat perencanaan dan agenda yang jelas.
Pembahasan dinamika militer dalam globalisasi ini menjadi tema buku ”Militer dan Globalisasi” karya Amarulla Octavian yang didasarkan pada monografi yang merupakan tugas dalam satu mata kuliah di Program Doktor Sosiologi Universitas Indonesia. Buku ini merupakan studi awal dan pengenalan tentang militer dan globalisasi dari perspektif sosiologi yang dapat membantu pembaca untuk memahami gejala tersebut. Analisis lengkap dengan kasus transformasi organisasi Sekolah Staf dan Komando TNI AL (SESKOAL) dalam menghadapi globalisasi telah menjadi topik disertasinya dan hasilnya diharapkan juga dapat dibukukan untuk melengkapi buku ini. Diharapkan buku ”Militer dan Globalisasi” ini dapat mengundang berbagai kalangan untuk lebih memahami, mengkritisi, dan siap menghadapi globalisasi, dalam arti menghadapi pengaruh globalisasi maupun menyumbang bagi globalisasi.
Depok, 4 April 2012
Iwan Gardono Sujatmiko
bab1-2 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 11 7/10/12 1:55 PM

12
Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan bagi saya untuk menulis buku ini, yang merupakan hasil pemikiran banyak pihak yang telah berjasa besar bagi saya, baik secara personal maupun tim. Buku ini sebenarnya merupakan pengembangan dari monografi yang telah saya susun dalam memenuhi persyaratan akademik selama menempuh program Doktor di Departemen Sosiologi, FISIP Universitas Indonesia. Oleh karena itu, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Iwan Gardono Sujatmiko, promotor saya, yang telah memberikan arahan, petunjuk dan kritik membangun atas karya ini. Saya juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Mas Bayu Asih Yulianto, M.Si., Mbak Nia Elvina, M.Si., dan Mas Arie Herdianto, M.Si., atas kerjasama timnya.
Masukan dan saran juga saya terima dari berbagai pihak yang menjadi mitra berdiskusi selama berlangsungnya proses penulisan, seperti Dr. Richardi Adnan, kolega-kolega saya Kolonel Inf Agus Rohman, Kolonel Pnb Sri Pulung Dwatmastu, S.E., M.MS., dan Kombes Pol Dr. Rycko Amelza Dahniel M.Si., serta teman kuliah saya Tantan Hermansah, M.Si. Kesemuanya sangat membantu dalam melengkapi bagian-bagian penting dan memberikan tanggapan-tanggapan yang proporsional. Untuk itu saya ucapkan beribu terima kasih. Selain itu juga penghargaan dan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Deniek G. Sukarya, editor saya, sekaligus designer grafis untuk buku ini.
Meskipun tidak dapat disebutkan satu per satu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada beberapa rekan, senior dan junior saya baik di kampus Universitas Indonesia maupun di Komando Armada RI Kawasan Barat dan di Korps Marinir,
Prakata Penulis
bab1-2 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 12 7/10/12 1:55 PM

13
yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan pandangan-pandangan yang konstruktif. Tak lupa saya juga sampaikan ucapan terima kasih kepada banyak pihak atas peran sertanya hingga diterbitkannya buku ini.
Saya berharap buku ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan yang berharga kepada kalangan luas dan melengkapi kajian atau studi tentang sosiologi militer. Semoga pola dan alur pemikiran dalam buku ini bermanfaat untuk mengantisipasi berbagai prediksi dan dinamika perkembangan keamanan pada tataran nasional dan global di masa mendatang. Buku ini juga dimaksudkan untuk mendorong para pemikir militer lainnya, khususnya di Indonesia, untuk lebih berperan mengeksplorasi gagasan dan ide-ide yang cemerlang guna memperkaya khasanah. Buku ini sengaja akan diterbitkan ke dalam beberapa versi bahasa guna menjangkau para pembaca di luar Indonesia, sekaligus dapat dimaknai sebagai upaya menambah kehadiran buku-buku Indonesia di pentas global.
Disadari sepenuhnya bahwa buku ini jauh dari kesempurnaan, dan untuk itu saya mohon maaf atas kesalahan dan/atau kekurangannya. Pada cetakan kedua ini telah dilakukan beberapa perbaikan sesuai masukan dari para pembaca. Selanjutnya, saya juga tetap mengharapkan berbagai saran dan kritik konstruktif demi kebaikan buku ini.
Akhir kata, penulisan buku ini juga tidak mungkin terselenggara tanpa doa restu dari kedua orangtua dan dukungan dari keluarga. Terima kasih atas limpahan cinta dan kasih sayangnya yang selama ini tiada hentinya diberikan kepada saya.Kepada para pembaca, saya ucapkan selamat membaca buku ini.Semoga bermanfaat.
Lagoi-Bintan, 2 Juni 2012
Amarulla Octavian
bab1-2 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 13 7/10/12 1:55 PM

14
bab1-2 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 14 7/10/12 1:55 PM

15
Bab I
Pendahuluan• Globalisasi dan Persoalan Keamanan• Sosiologi Militer
bab1-2 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 15 7/10/12 1:55 PM

16
Bab I
PendahuluanKajian-kajian mengenai persoalan militer di Indonesia, seringkali atau lebih banyak, terkait dengan peran militer dalam satu negara, termasuk di dalamnya yang membahas hubungan antara militer dan masyarakat ataupun kajian mengenai sejarah hubungan militer dengan negara dan rakyat. Sebagai sebuah negara yang merdeka di masa-masa akhir Perang Dunia Kedua dan mulai berkembang pada masa Perang Dingin, peran militer di Indonesia bisa dikatakan cukup besar dalam mendorong berbagai macam proses perubahan di dalam masyarakat dan negara. Terlepas apakah perubahan tersebut dimaknai secara positif ataupun negatif, ternyata beberapa peristiwa menunjukkan bagaimana keputusan-keputusan yang dilahirkan oleh institusi militer bisa menjadi energi yang kuat untuk mendorong elemen-elemen lain, seperti elemen sipil dan birokrasi untuk melakukan satu terobosan, terutama di ranah politik.
Meskipun tesis seperti ini bisa dianggap terlalu memposisikan militer lebih superior dibanding institusi lainnya, dalam perjalanan sejarah hal itu seringkali terbukti kebenarannya, seperti pada masa transisi politik 1960-an ketika TNI menjadi salah satu institusi yang mempelopori lahirnya Orde Baru serta proses Reformasi 1998 yang berjalan beriringan dengan reformasi di tubuh TNI. Apakah pasca Reformasi 1998 fenomena tersebut masih terjadi, belum ada satu penelaahan lebih jauh yang membahasnya. Namun dari dinamika politik terakhir, kita masih bisa saksikan bahwa institusi TNI mampu menjawab kebutuhan kepemimpinan yang dikehendaki oleh rezim reformasi sipil. Hal ini dibuktikan dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), seorang purnawirawan Jenderal TNI yang masih tetap dipercaya oleh sebagian besar Rakyat Indonesia untuk memimpin pemerintahan sipil meskipun diterpa beragam kritik. Walaupun demikian, kita juga harus mengakui bahwa pasca reformasi politik 1998, militer Indonesia telah mulai menjalankan agenda reformasi sebagai jawaban terhadap perkembangan politik yang terjadi. Beberapa nilai baru diadopsi disertai dengan penanggalan beberapa atribut kekuasaan yang pernah dipegang militer selama beberapa kurun waktu, seperti konsep Sosial Politik (Sospol) dalam Dwifungsi ABRI yang menyebabkan ABRI turut aktif di lembaga legislatif maupun eksekutif.1
Kondisi seperti di atas menunjukkan bahwa di samping memiliki peran dan posisi historis yang begitu kuat, organisasi militer Indonesia saat ini juga telah mengakomodasi berbagai perubahan ke arah posisi yang lebih selaras dengan situasi
1 Dwifungsi ABRI sebagai sebuah konsep mengalami pasang surutnya sejak masa Orde Lama, Orde Baru sampai dengan Orde Reformasi. Pada tahun 1958, Jenderal Purn A. H. Nasution menyampaikan ide dasar konsep tersebut sebagai konsep Jalan Tengah yang intinya untuk memberikan kesempatan sipil dan mi-liter bersama-sama membangun Indonesia. Tidak ada dikotomi sipil-militer. Pada tahun 1966, konsep tersebut diimplementasikan dalam bentuk Dwifungsi ABRI, yakni fungsi pertama Pertahanan-Keamanan (Hankam) dan fungsi kedua Sosial-Budaya (Sosbud). Perkembangan selanjutnya, pada tahun 1977 karena day-to-day politics, fungsi kedua berubah menjadi Sosial-Politik (Sospol).
bab1-2 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 16 7/10/12 1:55 PM

17
sosial maupun politik yang melingkupinya. Bahwa militer sebagai bagian dari institusi negara masih dilihat cukup kuat mempengaruhi kebijakan-kebijakan sipil, hal itu tidak dapat dipungkiri. Kendati demikian, mereka pada dasarnya juga akomodatif terhadap kritik dan isu dari luar yang menginginkan agar militer menjadi lebih profesional serta menerapkan norma-norma universal di bidang kemanusiaan dan demokrasi.
Pada titik ini, benar apabila sampai hari ini posisi dan peran militer dalam politik Indonesia memang masih menyita perhatian sejumlah pengamat. Namun demikian, dari beberapa sarjana yang menekuni isu mengenai militer, belum ditemui di antara mereka yang mencoba memasuki area yang lebih sensitif, yakni persoalan transformasi di dalam tubuh institusi militer itu sendiri. Transformasi yang terkait dengan tantangan-tantangan yang bukan saja menyoal perubahan kondisi sosial dan politik di Indonesia, melainkan juga pada tantangan ancaman keamanan global yang semakin hari semakin besar, plus dominasi wacana keamanan yang mungkin diserap oleh institusi militer Indonesia dari beberapa sarjana pemikir globalisasi. Mayoritas para sarjana lebih tertarik untuk membahas bagaimana peran dan posisi militer di dalam masyarakat yang lebih luas. Kalaupun ada yang berbicara tentang transformasi dalam tubuh institusi militer, seringkali mereka malah terjebak semata pada terminologi modernisasi teknologi dan organisasi semata. Masih sedikitnya sarjana yang berbicara mengenai transformasi itu sendiri merupakan sebuah kenyataan yang timbul sebagai akibat dari interaksi yang intens antara militer sebagai institusi negara dengan dinamika sosial dan ekonomi politik global dan persoalan-persoalan mendasar yang dialami oleh organisasi sosial. Pemahaman akan proses transformasi inilah yang kiranya bisa ditelaah melalui sudut pandang yang lebih sosiologik ketimbang hanya dari sudut pandang hukum, politik ataupun studi keamanan.
Oleh karenanya, diperlukan satu pemahaman sosiologis yang cukup untuk mengerti bagaimana institusi militer Indonesia berkembang dan berdinamika. Dengan pemahaman sosiologis itu, diharapkan kita bisa mengetahui dengan lebih dalam watak tradisional dari institusi militer Indonesia dan bagaimana pola transformasi semestinya dijalankan, terutama jika dikaitkan dengan tantangan keamanan global saat ini. Oleh karenanya, penting untuk melihat sejauh mana kajian-kajian atas perkembangan dan dinamika globalisasi yang ada sekarang ini memiliki korelasi jika dihubungkan dengan kajian sosiologi militer, terutama yang membahas mengenai persoalan kapasitas organisasi seperti kepemimpinan, teknologi, struktur dan hierarki serta doktrin. Secara ringkas, sebenarnya tesis ini bisa dikatakan sebagai upaya untuk membangun jembatan antara teori-teori globalisasi dan kajian sosiologi militer.
1.1.
Globalisasi dan Persoalan KeamananKata kunci yang paling tepat untuk menggambarkan keterkaitan, atau rantai penghubung antara globalisasi dengan militer adalah keamanan. Keamanan menjadi terminologi
bab1-2 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 17 7/10/12 1:55 PM

18
yang paling sering dibahas ketika kita menguak dinamika institusi militer dalam konteks globalisasi. Oleh karena itu, membahas persoalan keamanan dalam beberapa segi menjadi pokok kajian untuk mencari keterkaitan antara globalisasi dengan sosiologi militer.
Diskursus mengenai perkembangan dunia militer saat ini tidak terlepas dari dinamika globalisasi. Penjelasan-penjelasan mengenai perkembangan kekuatan militer di tiap-tiap negara mengarah pada satu upaya merespon perkembangan globalisasi yang mempengaruhi banyak segi kehidupan, khususnya yang terkait dengan persoalan keamanan global, kepentingan nasional, keamanan masyarakat, dan keamanan nasional serta persoalan yang menyangkut nilai-nilai universal saat ini, seperti kemanusiaan dan demokrasi. Keamanan telah menjadi isu yang sangat penting dalam diskusi dan pembicaraan para pemimpin dunia. Titik tolak seperti inilah yang pada gilirannya mendorong negara sebagai institusi yang memiliki organisasi militer secara resmi dan legal mulai memikirkan bagaimana mereka merespon perkembangan keamanan global.
Di sini, kita bisa melihat bagaimana dinamika institusional militer yang di dalamnya terkait dengan organisasi, teknologi, doktrin dan sumber daya manusia sangat berhubungan dengan bagaimana negara memandang keamanan itu sendiri, baik keamanan nasional, internasional maupun regional. Oleh karena itu tidak bisa dipungkiri, melakukan kajian yang mendalam terkait dengan dinamika globalisasi adalah satu-satunya pilihan yang harus dilakukan agar kekuatan militer di satu negara bisa berbenah dalam rangka menjawab tantangan yang muncul kelak di kemudian hari. Perbincangan seputar keamanan sendiri sudah pasti akan terkait dengan persoalan negara dan politik. Demikian juga halnya dengan globalisasi dan keamanan yang terkait erat dengan dinamika politik di satu negara. Inilah sebabnya mengapa persoalan militer dan globalisasi lebih tepat untuk didudukkan di dalam ranah sosiologi politik, karena persoalan keamanan berkaitan dengan konsep politik antara masyarakat dengan negara. Selaras dengan yang dijelaskan oleh Ayoob (2005) bahwa beragam pengaruh yang muncul akibat persoalan-persoalan ekonomi sampai lingkungan baru bisa dikatakan sebagai persoalan keamanan setelah melalui satu proses politik atau setelah melalui satu analisis politik. Ayoob dalam hal ini melihat bahwa konsep keamanan sudah semestinya diletakkan tidak dalam satu kerangka analisis yang terlalu lebar dan elastis sehingga justru menyebabkan analisis tersebut kehilangan kegunaannya. Ia menyarankan agar keamanan tetap dilihat sebagai satu konsep yang mengaitkan antara keteraturan dan otoritas, yang sudah pasti berkonotasi politik.2
2 Mohammad Ayoob menyarankan untuk menyelamatkan konsepsi keamanan dari terminologi kemanu-siaan itu sendiri, karena menurutnya persoalan keamanan adalah persoalan politik, bahkan penjelasan-pen-jelasan dari para sarjana yang memasukkan persoalan ekonomi dan lingkungan ke dalam ranah keamanan berpotensi membuat konsepsi keamanan itu sendiri kehilangan kegunaannya. Hal ini bukan karena per-soalan ekonomi dan lingkungan tidak bisa mempengaruhi keamanan satu negara, melainkan, persoalan ekonomi dan lingkungan itu sendiri menjadi persoalan keamanan ketika keduanya terlebih dahulu menjadi persoalan politik, seperti mengganggu kedaulatan negara atau melanggar perbatasan wilayah negara.
bab1-2 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 18 7/10/12 1:55 PM

19
Pasca Perang Dingin, bentuk-bentuk kejahatan yang menjadi ancaman terhadap persoalan keamanan sendiri semakin beragam. Dengan tiadanya pesaing bagi kekuatan politik Amerika Serikat (AS), kondisi ini memunculkan fenomena-fenomena kejahatan baru, terutama ancaman terhadap keamanan nasional atau negara. Salah satu manifestasi paling nyata yang tengah kita hadapi saat ini adalah persoalan terorisme yang menjadi isu keamanan paling mutakhir pasca Perang Dingin. Dalam penjelasan Paul (2005) juga diperoleh gambaran yang mengetengahkan bahwa perubahan ling- kungan politik yang terjadi pasca Perang Dingin memunculkan ketimpangan yang sangat jelas antara kesiapan organisasi militer yang dimiliki oleh negara dengan kemampuan teror yang dijalankan oleh organ-organ kekerasan, semisal pada serangan terorisme di WTC, New York, AS tahun 2001. Paul memberikan beberapa argumen mendasar mengapa institusi negara tampak tidak siap ataupun gugup dalam meng-hadapi pola-pola penyerangan semacam ini. Kegamangan tersebut di antaranya kare-na adanya pemahaman negara yang cenderung statis dalam memandang persoalan keamanan nasional itu sendiri. Sebelumnya persoalan ancaman keamanan yang dimaknai oleh masing-masing negara biasanya terkait dengan institusi negara lain yang memiliki kepentingan ekonomi dan politik terhadap negara mereka. Untuk itu, dalam memutuskan satu upaya penyerangan maupun penyerbuan akan memperhitungkan secara cermat untung dan rugi yang akan mereka peroleh ketika hal itu dilakukan. Tetapi saat ini, perhitungan tersebut tidak dilakukan dalam perspektif kejahatan terorisme. Selain itu, Paul juga menjelaskan mengenai pola-pola perubahan sasaran penye- rangan dari kelompok teroris. Target penyerangan teroris tidak lagi benteng-benteng pertahanan atau pangkalan-pangkalan militer dalam rangka menduduki satu wilayah atau teritori untuk dikuasai, namun lebih berupaya merusak simbol-simbol kekuasaan dan kejayaan satu rezim ataupun satu kekuatan ekonomi dan politik.
Penyerangan WTC dan markas Pentagon pada September 2001, serangan bom bunuh diri di Bali 2002 ataupun serangan bom bunuh diri di stasiun kereta api di Madrid 2004 dan di London 2005 membuktikan bahwa terorisme telah berubah seratus delapan puluh derajat dari apa yang pernah dipikirkan oleh negara, bahkan oleh analis politik sekalipun. Di sinilah letak argumen mendasar Paul bahwa negara belum siap menghadapi transformasi pola-pola kejahatan yang mengancam keamanan nasional pasca Perang Dingin.3
Dari kedua penjelasan di atas, kita bisa melihat betapa persoalan globalisasi dan keamanan adalah satu isu yang memiliki hubungan sangat erat. Globalisasi menyebabkan terjadinya pergeseran-pergeseran dalam perikehidupan manusia yang pada gilirannya juga membuat formasi-formasi kekuatan ekonomi politik dunia menjadi
3 Untuk lengkapnya, bisa dilihat pada tulisan T.V. Paul, “The National Security State and Global Terorism: Why The State is not Prepared for The New Kind of War ?” dalam Ersel Aydinli & James N. Rosenau (ed), Globalization, Security and Nation State, ( State University of New York, 2005)
bab1-2 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 19 7/10/12 1:55 PM

20
berubah. Yang pada gilirannya juga membuat pola-pola konflik kepentingan bergeser sehingga dalam beberapa hal konflik itu tidak dapat dikelola sehingga muncullah beberapa ancaman terhadap keamanan nasional satu negara. Dalam konteks ini, kiranya penjelasan Ersel Aydinli (2005) yang menyimpulkan adanya tiga hal mendasar yang perlu diperhatikan dalam melihat persoalan globalisasi dan keamanan, penting untuk dikemukakan di sini: Pertama, perubahan yang terjadi secara terus menerus dalam konteks globalisasi menjadikan segala sesuatu - dalam hal ini, persoalan keamanan - memiliki unsur ketidakpastian (uncertainty). Ketidakpastian itu pada gilirannya juga mendorong berbagai pihak yang berkecimpung dalam isu keamanan untuk selalu memasukkan faktor perubahan dan ketidakpastian itu dalam setiap analisanya. Kedua, persoalan kekuasaan (power), konfigurasi kekuasaan yang menjadi latar dari berbagai konflik dan ketegangan yang pada gilirannya menjadi ancaman terhadap keamanan suatu negara menjadi penting untuk diperhatikan dalam rangka melihat relasi dan jaringan yang terkait dengan ancaman terhadap keamanan nasional. Ketiga, persoalan dualitas antara konsepsi mengenai negara - traditional state-centric dan multistate-centric. Pada gilirannya dua konsepsi negara dalam hubungan internasional tersebut tidak saling meniadakan atau menghilangkan satu sama lain.
Beberapa pandangan tersebut pada gilirannya memicu timbulnya pertanyaan-pertanyaan mendasar yang terkait dengan bagaimana sesungguhnya beragam panda- ngan yang menjelaskan mengenai hubungan antara globalisasi dan persoalan keamanan terpetakan berdasarkan mazhab pemikiran yang dianut oleh para sarjana tersebut, termasuk manifestasi paling kongkret dari hubungan yang telah ada.
1.2. Sosiologi MiliterSosiologi militer, sebenarnya adalah bagian dari ilmu sosiologi yang secara khusus membahas mengenai hubungan antara militer dan masyarakat sipil. Kajian ini sesungguhnya mencerminkan kenyataan empiris bahwa sebagai sebuah institusi yang diberikan hak secara legal untuk melakukan tindakan keras terorganisir oleh negara, militer pada gilirannya menjadi salah satu organisasi sosial yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Pendekatan ini menggambarkan satu hasil perkembangan atau perubahan sosial di dalam masyarakat dunia yang semakin ingin memposisikan militer di bawah otoritas sipil atau bagian dari masyarakat itu sendiri, sehingga keputusan-keputusan yang terkait dengan urusan militer bisa juga ditangani atau dicampuri oleh kekuatan sipil, atau lebih tepatnya dalam konteks masyarakat dewasa ini, kajian sosiologi militer bisa dilihat sebagai satu bentuk representasi sipil di dalam ranah militer. Sosiologi militer sangat berbeda dengan geopolitik, karena geopolitik yang merupakan ranah kajian ekonomi politik lebih mengedepankan konteks geografis satu negara dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Sementara sosiologi militer memiliki cakupan yang lebih luas dan bahkan geopolitik bisa menjadi salah satu bagian yang dibahas dalam ranah kajian sosiologi militer satu negara.
bab1-2 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 20 7/10/12 1:55 PM

21
Pertanyaannya kemudian, bagaimana sosiologi militer sebagai ranah dalam disiplin ilmu sosiologi itu berkembang sampai sekarang ini, termasuk para pemikir-pemikir pelopor sampai yang kontemporer. Dalam konteks Indonesia, pendekatan sosiologi militer masih sangat langka dimanfaatkan, namun tidak bisa pula dikatakan tidak ada sama sekali. Memang, kajian-kajian mengenai militer cukup banyak dilakukan oleh para sarjana-sarjana ilmu politik ataupun sejarawan atau para sarjana yang menekuni kajian pertahanan dan keamanan. Hal ini tentu amat sangat berbeda dengan pende-katan yang sifatnya sosiologis. Paling tidak perbedaan itu bisa dilihat dari perspektif atau cara pandang seorang sarjana dalam melihat persoalan-persoalan militer, baik institusinya maupun relasinya dengan struktur sosial di masyarakat dan negara.
Dalam konteks kajian ini, setelah sebelumnya dibahas mengenai persoalan globalisasi dan masalah keamanan, maka pada gilirannya pertanyaan berikut haruslah juga dicarikan jawabannya: bagaimana perkembangan masalah keamanan yang terpengaruh oleh perubahan global memiliki keterkaitan dengan persoalan militer, baik hubungannya dengan masyarakat, maupun dengan dinamika institusional, terutama yang terkait dengan proses transformasi yang dijalankan sebagai konsekuensi logis dari tantangan keamanan global itu sendiri.
Sebagai pengantar, latar belakang permasalahan ini tentu saja menjadi penting untuk dijelaskan dalam kerangka mencari benang merah yang bisa menjawab perta-nyaan pokok dari kajian ini, yakni, sejauh mana persoalan keamanan dalam konteks global memberikan sumbangan pemikiran pada ranah kajian sosiologi militer, terutama di Indonesia. Dengan adanya pertanyaan ini, diharapkan akan ada jawaban yang lebih kongkrit tentang bagaimana Indonesia sebagai sebuah negara yang semakin diperhitungkan keberadaannya di dunia internasional akan menyikapi dan menghadapi globalisasi dalam bidang keamanan, terutama ketika muncul tuntutan agar institusi militernya berbenah dalam rangka transformasi diri. Kendatipun demikian, dalam konteks Indonesia yang memiliki sejarah penjang dalam dominasi militer dalam dunia politik, pertanyaan ini juga menyiratkan satu bentuk optimisme bahwa perubahan yang cukup fundamental pada tatanan struktur politik Indonesia pasca reformasi mendorong terjadinya perubahan yang mendasar dalam konteks hubungan antara sipil dan militer sehingga tuntutan akan transformasi itu sendiri muncul tidak hanya dari kelompok masyarakat, melainkan juga dari dalam tubuh militer itu sendiri. Hal inilah yang sekiranya bisa dijelaskan melalui perspektif sosiologik, utamanya sosiologi militer.
Dalam konteks kajian sosiologi, perkembangan pemikiran yang menempatkan dialektika agen-struktur dan resiprositas agen-struktur menjadi bentuk penelaahan teoritik paling akhir selain kajian-kajian mengenai post modern4 juga perlu diteliti
4 Para pemikir seperti Pierre Bourdieu dan Anthony Giddens adalah mereka yang sedikit banyak mewakili pemikiran mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial seperti ini. Interaksi sosial yang lebih dinamis, ter-utama ketika berkait dengan bagaimana perubahan itu muncul, bertahan, dan hilang. Hal ini tentu saja akan memberikan nuansa pemikiran yang cukup berbeda ketimbang, para sosiolog yang secara genealogis terpisah akibat perdebatan antara perilaku agensi maupun determinasi struktur sosial.
bab1-2 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 21 7/10/12 1:55 PM

22
lebih lanjut. Dengan cara pandang yang demikian, diperoleh satu pemahaman bahwa fenomena mempengaruhi dan dipengaruhi antara agen dengan struktur dan sebaliknya, terutama dalam masyarakat dunia di mana interaksi sosial semakin hari semakin tidak terbatas terkesan menjadi begitu longgar. Pemahaman mengenai dikuasai dan menguasai, dipengaruhi dan mempengaruhi ataupun diakibatkan dan mengakibatkan, senantiasa memiliki konteks. Namun, hal itu tidak lantas bisa berlangsung terus menerus dalam satu jalinan hubungan, terutama yang bersifat jangka panjang. Adanya kemungkinan agen mempengaruhi struktur atau struktur yang memaksa agen memberikan beragam kemungkinan bagaimana perubahan ataupun transformasi itu bisa dikelola dan dipertahankan, ataupun digagalkan. Oleh karenanya, globalisasi keamanan nasional dan transformasi militer di Indonesia haruslah dilihat dan diperlakukan dalam konteks pemahaman di atas.
Buku ini terdiri dari delapan bab, masing-masing mengetengahkan persoalan yang berbeda, tetapi dasar permasalahannya masih tetap sama, yakni kebutuhan untuk menjawab bagaimana keterkaitan antara persoalan keamanan, globalisasi, institusi militer dalam satu cara pandang yang masih sangat jarang digunakan, yakni cara pandang yang sifatnya sosiologis. Oleh karena itu, dalam bab pertama disajikan latar belakang dari persoalan mengenai globalisasi dan masalah keamanan secara umum serta pengenalan perspektif sosiologik dalam membedah persoalan militer. Pengantar di bagian awal ini diharapkan bisa membantu para pembaca untuk lebih singkat memahami apa yang menjadi isu pokok dari buku ini.
Selanjutnya, pembahasan mengenai diskursus pemikiran globalisasi dan keamanan nasional disajikan di dalam bab kedua. Perdebatan-perdebatan teoritis seputar bagaimana para sarjana memandang globalisasi dan keamanan nasional menjadi inti dari bagian ini. Selain itu di bagian akhir dari bab ini juga dilengkapi dengan tabel pemetaan teoritik dari para sarjana yang membahas masalah globalisasi dan keamanan dari sudut pandang sosiologi militer.
Bab ketiga dari buku ini menyajikan isu pokok dari perkembangan transformasi militer di dunia, yaitu Revolutionary in Military Affairs (RMA). Sebuah terminologi yang lahir di masa-masa Perang Dingin dan dalam perjalanannya banyak diadopsi oleh negara-negara di dunia. Banyak negara yang menganggap RMA adalah sesuatu yang harus dijalani ketika tuntutan mengenai modernisasi militer harus dilakukan demi terjaminnya keamanan nasional negara mereka. Pada bagian ini juga diketengahkan konsekuensi-konsekuensi sosiologis ketika RMA dijalankan oleh sebuah negara. RMA yang mendorong kemajuan pada industri teknologi militer pada gilirannya juga dibarengi oleh transformasi dari bentuk-bentuk konflik yang ada di dunia serta semakin canggihnya tindakan kejahatan yang terorganisir (transnational organized crime).
Sebagai bentuk pembahasan lanjutan dari RMA, pada bab keempat diketengahkan pengalaman transformasi militer dari negara-negara yang ada di dunia. Pengalaman transformasi ini mencakup bagaimana gagasan mengenai transformasi militer nasional
bab1-2 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 22 7/10/12 1:55 PM

23
itu muncul dalam konteks dinamika ekonomi politik di masing-masing negara serta praktik-praktik transformasi yang mereka lakukan. Untuk melengkapi pembahasan di dalam bagian ini, disajikan beberapa contoh praktik transformasi militer dari beberapa negara di Eropa dan Asia. Selain itu, ada juga perbandingan transformasi militer dari dua negara besar dunia, yakni AS dan Cina.
Untuk mengkontekstualisasikan kajian yang dilakukan, maka pembahasan mengenai perkembangan globalisasi dan keamanan nasional di bab kelima diarahkan pada perkembangan institusional militer Indonesia dari waktu ke waktu. Dalam perkembangan sejarahnya, TNI menunjukkan bagaimana dinamika yang terjadi pada level global memiliki pengaruh yang signifikan bagi perkembangan organisasi TNI itu sendiri. Tentu saja hal ini tidak terlepas dari dinamika sosial dan politik yang terjadi pada level negara.
Untuk melengkapi pembahasan dari kerangka teoritik dan praktik-praktik transformasi di berbagai negara termasuk Indonesia, pada bab keenam dan ketujuh dari buku ini disajikan uraian atas pertanyaan-pertanyaan kunci yang telah disebutkan pada bagian awal. Bab keenam menyajikan skenario awal dari proses transformasi yang bisa dilakukan oleh TNI. Skenario ini disebut sebagai skenario awal karena lebih merujuk pada argumentasi-argumentasi pokok yang menjadi basis dari alasan transformasi itu sendiri. Untuk itu, pembahasan pada bagian ini dibagi menjadi dua level, nasional dan global. Pembagian itu sendiri berangkat dari pendefinisian atas lingkungan global dalam urusan keamanan nasional. Sementara pada bab ketujuh, penulis mengabstraksikan pembahasan-pembahasan sebelumnya ke level teoritik. Tafsir teoritik ini, selain dalam rangka menjawab kebutuhan akademik juga sebagai upaya untuk mendorong berbagai pihak untuk bisa membedah persoalan-persoalan militer di Indonesia dalam perspektif yang berbeda, yakni perspektif sosiologik. Penggunaan perspektif sosiologik dalam mempelajari interaksi sosial di dalam tubuh militer baik pada level makro, meso maupun mikro pada prosesnya bukan saja terkait dengan kerja-kerja akademik, melainkan sebagai praktik sosial yang bisa lebih berkontribusi menyelesaikan persoalan-persoalan sosial baik di dalam tubuh militer, maupun di dalam konteks hubungan institusi militer dengan institusi sosial lainnya.
Bagian terakhir dari buku ini adalah bab kedelapan yang menyajikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dalam buku ini. Pada bagian ini dirangkum jawaban-jawaban pokok dari pertanyaan-pertanyaan esensial yang telah diajukan di bagian awal dari buku ini. Intinya adalah sebuah pembuktian bahwa dari kajian-kajian mengenai globalisasi, keamanan nasional dan sosiologi militer, institusi militer adalah institusi sosial yang pastinya, semestinya dan seharusnya menjadi yang paling adaptif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dunia.
bab1-2 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 23 7/10/12 1:55 PM

24
bab1-2 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 24 7/10/12 1:55 PM

25
Bab II
Diskursus Globalisasidalam Kajian Militer• Pandangan Globalisasi Anthony Giddens dan Kajian Sosiologi Militer• Gagasan Regionalisme Ekonomi Kenichi Ohmae• Keith Faulks: Mengembalikan Negara• Jonathan Krishner dan Persoalan National Security• Studi Empirik Norin Ripsman dan T.V. Paul• Rangkuman
bab1-2 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 25 7/10/12 1:55 PM

26
Bab II. Diskursus Globalisasi dalam Kajian Militer Sebagai sebuah entitas yang memiliki sistem dan struktur tersendiri, masyarakat militer merupakan sebuah arena studi yang menarik. Terlebih lagi, dalam rentang yang sangat panjang, entitas ini telah mengharubiru struktur masyarakat manapun di dunia. Kebanyakan, sosiolog yang besar dan lahir dalam kultur masyarakat Italia bahkan menjadikan masyarakat militer sebagai entitas yang memiliki tempat istimewa. Gramsci, Vareto, dan banyak lagi menjelaskan betapa keberperanan kelompok ini demikian penting dalam studi-studi mengenai masyarakat.
Bagian berikut dari buku ini akan mendiskusikan pandangan para teorisi—khususnya sosiolog dalam mengkaji masyarakat militer di dunia. Dengan mengajukan kerangka seperti ini, maka kita bisa melihat mengapa studi militer dalam ranah sosiologis menjadi sangat penting dilakukan.
2.1. Pandangan Globalisasi Anthony Giddens dan Kajian Sosiologi Militer
Perhatian besar para akademisi terhadap globalisasi dimotivasi oleh ketertarikan dan sekaligus kecemasan mereka terhadap globalisasi. Giddens, adalah salah satu akademisi yang melihat kaitan antara globalisasi dan risiko yang direkayasa (manufactured risk) (Ritzer, 2003). Pandangan Giddens ini sangat berkaitan dengan konsep modernisasi yang dikajinya. Modernisasi di satu sisi memunculkan sisi positif atau kemajuan tetapi di sisi lain juga menimbulkan berbagai risiko. Yang kedua ini merupakan hasil atau konsekuensi yang tidak diharapkan dari modernisasi. Modernisasi ini menurut Giddens dimulai dengan munculnya institusi-institusi penopangnya seperti kapitalisme, industrialisme, kemampuan mengawasi aktifitas warga negara dan pengendalian atas alat-alat ke-kerasan termasuk industrialisasi peralatan perang. Modernisasi juga memunculkan pemisahan waktu dan ruang. Waktu distandarisasi. Sementara ruang makin lama makin dilepaskan dari tempatnya. Dengan adanya pemisahan ini memunculkan birokrasi dan negara bangsa serta kemampuannya untuk menghubungkan otoritas lokal dan global. Pemisahan ini merupakan salah satu sumber utama dinamisme dalam modernitas. Akan
bab1-2 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 26 7/10/12 1:55 PM

27
tetapi keterpisahan ini juga menimbulkan sejumlah masalah. Intensitas risiko yang dimunculkan oleh modernitas menjadi risiko yang berskala global, misalnya ancaman perang nuklir atau ancaman terorisme. Hal ini mengakibatkan perasaan yang tidak aman atau ketidakpastian dalam dunia modern. Proses modernisasi seperti “panser raksasa” (juggernaut) yang melaju tanpa terkendali sehingga dampak yang ditimbulkannyapun mempunyai risiko yang tinggi bagi keberlanjutan kehidupan dunia. Kemudian muncul pertanyaan mengapa realisasi modernisasi menjadi demikian. Berkaitan dengan hal ini, Giddens mengindentifikasi empat faktor penyebab: Pertama, kesalahan rencana dalam menentukan unsur-unsur dunia modern. Kedua, kesalahan dari operator yang menjalankan modernisasi. Ketiga, akibat tak diharapkan dari sistem modernisasi tersebut. Keempat, refleksifitas pengetahuan sosial; artinya pengetahuan yang baru secara terus menerus melahirkan sistem menuju arah yang baru.
Untuk itu, menurut Giddens globalisasi harus dipahami sebagai berbagi risiko yang ditimbulkan oleh modernitas tadi; restrukturisasi cara-cara kita menjalani hidup dan melalui cara yang sangat mendalam. Supaya dunia ini menjadi lebih terkendali, maka negara-negara harus berkerjasama karena globalisasi menurut Giddens merupakan proses yang berjalan dua arah antara bangsa-bangsa Barat dan negara-negara di luar Barat. Globalisasi menghasilkan area baru yang melintasi bangsa-bangsa.
Sementara itu, pada satu sisi globalisasi selain menimbulkan kosmopolitanisme atau hegemoni AS atau Barat baik dalam aspek ekonomi dan kebudayaan; pada sisi yang lain juga menimbulkan fundamentalisme dan juga sekaligus menguatkan budaya lokal. Wujud fundamentalisme ini bisa dalam bentuk atas nama etnis, agama, nasionalisme dan sebagainya. Dan hal ini menyebabkan persoalan baru yakni persoalan keamanan. Karena dengan adanya globalisasi, fundamentalisme ini juga bisa melintasi ruang dan waktu, seperti kasus-kasus terorisme dan berbagai kasus lainnya. Oleh karena itu, tesis yang dibangun oleh Giddens yakni globalisasi harus dipahami sebagai berbagi risiko dalam dunia yang demokratis khususnya negara-negara yang bisa menjadi agen seperti AS atau Barat atau juga di belahan Asia seperti Cina.
Melalui cara pandang seperti ini, Giddens menawarkan satu bentuk pemikiran yang ingin memposisikan globalisasi menjadi satu bentuk konteks dari interaksi sosial yang terjadi di seluruh dunia. Globalisasi tidak lantas serta merta serba Barat atau Amerikanisasi, melainkan juga membuka peluang munculnya nilai-nilai lokal di ranah global (glokalisasi). Oleh karena itu tawaran untuk membangun kerangka kerjasama di antara negara-negara di dunia dalam rangka menghadapi risiko-risiko keamanan yang senantiasa bisa muncul dianggap dapat menjadi jalan keluar untuk meminimalisasi
bab1-2 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 27 7/10/12 1:55 PM

28
kerugian ataupun kesulitan-kesulitan yang akan ditemui oleh masyarakat dunia di masa depan. Sebagai contoh kongkret, lihat saja masalah-masalah kesehatan seperti ancaman wabah pandemik flu burung ataupun SARS ataupun bencana alam yang kerap melanda wilayah-wilayah di dunia, persoalan perubahan iklim dan peperangan yang terjadi di kawasan-kawasan rawan konflik membutuhkan adanya semangat dari negara-negara untuk menciptakan berbagai pranata baru yang bisa memungkinkan adanya satu mekanisme pembagian risiko yang lebih adil.
Dalam pandangan Giddens pula, kita seperti disadarkan bahwa tidak ada lagi tempat di mana kita bisa berlindung dari pengaruh serta dampak dari globalisasi itu sendiri. Setiap kelompok masyarakat di dunia ini mau tidak mau, sadar tidak sadar, adalah bagian dari proses globalisasi yang oleh Giddens digambarkan seperti panser raksasa itu tadi. Ia tidak bisa dihentikan, ia tidak bisa ditolak, dan juga ia mengakibatkan beragam konsekuensi atau risiko. Namun yang pasti, Giddens juga menekankan bahwa globalisasi telah menurunkan derajat keterpusatan Barat. Jelaslah bahwa konsepsi juggernaut itu sendiri berlaku bukan hanya bagi pihak non produsen nilai-nilai global, ia juga menggilas pihak-pihak yang memproduksi panser raksasa itu sendiri. Globalisasi mengakibatkan kekuasaan di dunia semakin tersebar dan ini juga berlaku bagi negara bangsa Barat. Di satu sisi globalisasi memperkuat pengaruh mereka, tetapi di sisi yang lain globalisasi juga mengurangi porsi kekuasaan mereka.
Pembahasan paling fundamental dari konsep-konsep sosiologi Giddens tentu saja adalah seberapa jauh relasi agen dan struktur saling mempengaruhi dalam satu proses konstruksi sosial di masyarakat. Demikian juga dengan kemampuannya untuk kembali mengetengahkan agen sebagai pihak yang memiliki kemampuan untuk terlibat secara aktif dalam satu proses strukturasi itu sendiri. Jika ditarik ke dalam pembahasan mengenai globalisasi, keamanan nasional serta keberadaan institusi militer, apa yang oleh Giddens dikatakan sebagai proses strukturasi, barangkali bisa dilihat sebagai satu proses di mana globalisasi secara singkat bisa dikatakan sebagai satu struktur yang mendorong terjadinya reorganisasi struktur dari institusi negara khususnya lembaga militernya dalam menjawab tantangan dan masalah global sekaligus mengupayakan diri untuk bisa terlibat dalam upaya mengkonstruksi aturan main global terkait persoalan keamanan.
Kendati Giddens secara tegas mengatakan bahwa globalisasi melintasi batas-batas teritorial negara dan bangsa, kesan yang kita dapat bahwa ia masih tetap menaruh harapan terhadap keberadaan negara bangsa (nation state) itu sendiri. Tawaran-
bab1-2 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 28 7/10/12 1:55 PM

29
tawarannya bisa dikatakan masih menempatkan negara sebagai faktor esensial dari upaya pengurangan risiko yang diakibatkan oleh bekerjanya globalisasi itu sendiri.
Kajian Mengenai Sosiologi MiliterSosiologi militer mulai menjadi ranah kajian yang intens di dalam bidang sosiologi sejak Perang Dunia Kedua. Muncul dua tradisi dalam kajian ini (Eric, 2005). Tradisi pemikiran yang pertama lebih memfokuskan kajiannya pada relasi antara masyarakat sipil dan militer yang diprakarsai oleh Samuel Huntington dengan karyanya The Soldier and The State pada tahun 1957. Huntington mencoba menganalisis bagaimana interaksi antara kekuatan militer dengan otoritas masyarakat sipil, baik di negara-negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokratis maupun di negara-negara yang masih dalam tahap mencapai sistem pemerintahan yang demokratis seperti negara-negara di Afrika Selatan. Sedangkan tradisi pemikiran yang kedua, lebih memfokuskan kajiannya pada militer sebagai organisasi atau dengan kata lain sebagai sebuah institusi sosial. Kajian ini diprakarsai oleh Morris Janowitz dengan karyanya The Professional Soldier tahun 1960. Menurut Janowitz, analisis institusi tidak hanya mencakup institusi militer (perang dan damai), tetapi juga mencakup relasi militer dan masyarakat sipil, pengurangan angkatan atau senjata perang, penjagaan perdamaian, serta menajemen dan reduksi konflik. Morris juga menegaskan bahwa masyarakat itu sangat dinamis sehingga dunia militer pun harus mempunyai daya adaptasi yang tinggi.
Kajian yang dikembangkan oleh Janowitz bersifat lebih holistik dibandingkan dengan Huntington. Hal ini disebabkan karena kajian yang dikembangkan oleh Janowitz merupakan pengembangan dari kajian-kajian sebelumnya dari ranah sosiologi militer termasuk di dalamnya kajian yang telah dilakukan oleh Huntington. Dalam karya klasiknya tersebut, Janowitz menemukan bahwa organisasi militer di Barat semakin meningkatkan profesionalisme mereka, baik dalam sikap maupun dalam keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi sebagai militer modern.
Sementara itu, perdebatan yang paling hangat yang terjadi di dalam ranah kajian sosiologi militer adalah perdebatan tentang posisi sosiologi militer dalam sosiologi. Caforio (2003) mengemukakan bahwa sosiologi militer merupakan sub bagian dari sosiologi. Ia menempati posisi seperti sosiologi pendidikan, sosiologi agama, sosiologi gender. Akan tetapi argumentasi yang dibangun oleh Caforio ini kurang mumpuni untuk menjelaskan misalnya fenomena tentang perempuan dalam militer yang hanya dapat dijelaskan melalui pendekatan sosiologi gender. Atau relasi antara militer dan
bab1-2 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 29 7/10/12 1:55 PM

30
masyarakat sipil yang dapat dijelaskan oleh pendekatan sosiologi politik. Dengan adanya realitas demikian, maka para sosiolog yang mendalami kajian tentang militer menyepakati bahwa posisi sosiologi militer adalah bidang sosiologi yang umum dalam sosiologi (Eric, 2005) sehingga mereka lebih fleksibel untuk memanfaatkan analisis-analisis sosiologi tentang militer.
Jika kita cermati dengan seksama dari berbagai kajian dalam ranah sosiologi militer baik yang berasal dari tradisi Huntington maupun Janowitz, pendekatan yang mereka gunakan berakar dari pendekatan fungsionalis. Analisis yang sangat menekankan keteraturan sistem. Fungsi dan disfungsi komponen-komponen yang membentuk sistem militer sehingga muncul pendekatan lain yang disebut dengan pendekatan Weberian (pendekatan interpretatif). Tradisi pendekatan ini berakar dari pemikiran filsuf Immanuel Kant. Menurut Kant, universalitas dibangun dari kebenaran yang apriori. Kebenaran yang apriori diturunkan dari pemikiran tentang proposisi-proposisi yang berasal dari bukti. Kemudian ide Kant ini dikembangkan oleh Dilthey dengan konsep dari Max Weber yang terkenal, yaitu pemahaman (Verstehen). Artinya untuk memahami realitas sosial, maka dapat dilihat dari pemahaman atau pemaknaan dari aktor sosial. Selanjutnya Max Weber mengembangkan ide ini untuk memahami kelompok-kelompok sosial, dan terutama sekali organisasi. Weber mengembangkan konsep tipe ideal sehingga pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan interpretatif, karena sosiolog melakukan interpretasi untuk memahami realitas sosial, termasuk realitas tentang dunia militer. Melalui pendekatan ini kita dapat memahami bagaimana gagasan lama dan gagasan baru mempunyai peranan yang penting dalam proses perubahan institusi militer. Contohnya: kita dapat memahami mengapa seseorang mau menjadi seorang tentara dan bagaimana kebijakan mengenai sumber daya manusia mengadaptasi sesuai motif ini. Berdasarkan perspektif interpretatif ini, maka kita dapat menentukan tipe ideal tentara dan perubahannya untuk mencapai hal itu.
Selanjutnya, gagasan utama dalam sosiologi militer adalah militer dipandang sebagai sebuah organisasi kekerasan. Sosiologi militer merupakan sosiologi tentang organisasi kekerasan (Eric, 2005). Kekerasan merupakan obyek studi dari sosiologi militer. Kita tidak dapat menolak bahwa kekerasan merupakan sebuah realitas sosial, baik yang bersifat potensial maupun yang telah terjadi (manifest). Kekerasan dapat kita lihat dalam berbagai bentuk dan melalui berbagai aliran. Berkaitan dengan hal ini, menurut Eric (2005) pendekatan interpretatif sangat tepat untuk menjelaskan hubungan antara masyarakat sipil dengan organisasi kekerasan ini (militer).
bab1-2 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 30 7/10/12 1:55 PM

31
Walaupun demikian, kedua pendekatan di atas belum cukup untuk menjelaskan
berbagai isu dalam dunia militer. Pendekatan interpretatif cenderung mengabaikan peran
struktur dalam mempengaruhi tindakan agen atau aktor. Sedangkan pendekatan fungsionalis
di satu pihak mengabaikan peran agen atau aktor dalam mempengaruhi atau membentuk
ulang sistem. Walaupun pendekatan kritis juga mulai dikembangkan tetapi kajian mereka
dianggap belum terlalu tepat untuk menjelaskan dengan baik dinamika yang terjadi dalam
dunia militer (Eric, 2005). Akan tetapi, kembali kepada argumentasi yang dikemukakan
oleh Janowitz sebelumnya bahwa dinamika dalam masyarakat sangatlah dinamis dan
kompleks. Begitu juga dengan dinamika yang terjadi dalam dunia militer sehingga hal ini
memungkinkan untuk menganalisis fenomena dalam dunia militer dengan menggunakan
perspektif yang terbaru, misalnya kecenderungan dalam ilmu sosiologi untuk menggunakan
analisis agen-struktur.
2.2. Gagasan Regionalisme Ekonomi Kenichi Ohmae
Kenicihi Ohmae mencoba melihat perkembangan perekonomian dunia pasca Perang
Dingin. Menurutnya, globalisasi dalam bidang ekonomi, pada kenyataannya melunturkan
batas-batas teritori suatu negara. Meskipun penjelasan Ohmae atas globalisasi ini cenderung
digolongkan sebagai tafsir “kanan”, tapi pada dasarnya, ia juga seperti Marx dan Engels
yang mengakui bahwa ada aliran riil aktivitas ekonomi yang sifatnya mondial.5 Artinya,
ekonomi adalah faktor penentu dari masifnya perubahan sosial di masyarakat akibat
globalisasi itu sendiri. Negara sebagai aktor penting yang secara kasat mata bisa dikatakan
sebagai pembatas atas masyarakat dan globalisasi, mesti memahami bahwa globalisasi
adalah semata hanya persoalan aliran ekonomi yang menjalar ke segala arah, sehingga
sebisa mungkin, globalisasi ditangkap sebagai peluang kemajuan ekonomi suatu bangsa
dan bukan ancaman.
Dalam bukunya The End of The Nation State pada tahun 1995, Ohmae mencoba
menjelaskan perihal “the four I”s”, yaitu investment, information technology, industry dan individual consumers. Keempat hal itulah yang menurutnya menjadi penggerak dari aliran
ekonomi global. Investasi pasar modal berkembang sangat cepat pasca Perang Dingin.
Dengan bantuan teknologi, aliran keuangan global semakin cepat dan bahkan dalam
5 Keterangan yang mengatakan bahwa Ohmae adalah penafsir globalisasi aliran kanan atau memiliki kecenderungan neo liberal salah satunya adalah David Korten, dalam bukunya When Corporation Rule The Word. (1995). Kumarian Press.
bab1-2 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 31 7/11/12 11:23 AM

32
beberapa hal menghilangkan kontrol negara atas proses transaksi yang sedang berlangsung.
Investasi seperti ini juga pada dasarnya didorong oleh kelompok korporasi internasional.
Pergerakan modal dari korporasi-korporasi ini juga sangat cepat, bukan saja berlangsung di
negara-negara maju, melainkan juga mulai memasuki negara-negara berkembang di Asia.
Selain karena inovasi teknologi yang sedemikian dahsyat, proses globalisasi
juga mendorong investasi di bidang sumber daya manusia.6 Perkembangan investasi
korporasi industri untuk meningkatkan sumber daya manusia selanjutnya didorong oleh
adanya kesadaran individu-individu dalam masyarakat untuk mengkonsumsi barang
dan jasa sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kenyataan ini kemudian mendo-
rong munculnya satu kebutuhan untuk membuka industri baru dalam rangka memenuhi
kebutuhan masyarakat tersebut. Industri bukan saja memerlukan tenaga kerja dan
lahan, tetapi juga kemampuan untuk bisa menghasilkan barang dengan harga yang relatif
murah sehingga konsekuensinya adalah industri membutuhkan tenaga kerja dan lahan
yang murah. Negara berkembang dalam keadaan seperti ini menjadi pilihan yang paling
rasional untuk mengalirkan modal dalam rangka membangun industri-industri baru yang
membutuhkan lahan dalam jumlah besar serta tenaga kerja yang banyak, terampil dan
murah. Sementara industri yang sedikit tenaga kerja dan sedikit penggunaan lahan, tetap
bisa dibangun di negara-negara maju.
Inti dari gagasan Ohmae yang paling penting dalam konteks kajian ini ada dua, yang
pertama, peran negara yang semakin kecil akibat proses globalisasi yang menghilangkan
batas-batas teritori negara. Dengan cara pandang seperti ini, kiranya Omahe berusaha
untuk mengatakan bahwa mengurangi peran negara adalah satu-satunya jalan agar manfaat
globalisasi yang dianggap bisa menghilangkan sistem ketidak-adilan yang dialami oleh
masyarakat bisa betul-betul terwujud. Jika ditarik ke dalam agenda kebijakan ekonomi
politik satu negara, maka deregulasi menjadi kata kunci dari bagaimana negara seharusnya
menjawab tantangan globalisasi itu sendiri. Melakukan proteksi hanya akan menurunkan
derajat suatu negara dalam konteks persaingan global antar negara. Pembatasan-pembatasan
atas investasi asing, kontrol pemerintah yang sangat besar dalam perekonomian, regulasi
yang tidak berpihak pada pasar, menurut Ohmae, hanya akan merugikan negara bangsa
itu sendiri. Sebab menurutnya dalam ekonomi tanpa batas dari sebuah dunia yang saling
tergantung, yang dibutuhkan bukanlah kedaulatan lokal atas kesulitan-kesulitan lokal,
6 Lihat penjelasan Keith Faulks mengenai Omahe dalam Political Sociology : A Critical Introduction, (Edinburgh University Press, 1999) hal.56.
bab1-2 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 32 7/11/12 11:24 AM

33
tetapi justru deregulasi yang mengurangi hambatan-hambatan.
Ekonomi global bisa membantu memberikan berbagai solusi atas persoalan-persoalan
itu.7 Oleh karenanya, faktor kepemimpinan yang kuat untuk bisa membawa suatu negara
memenangi pertarungan global menjadi sangat penting. Dan seorang pemimpin yang baik,
mestilah mampu menerima kenyataan bahwa banyak hal yang tidak lagi bisa dikelola ataupun
diurus langsung oleh negara. Dengan kata lain, untuk menghadapi globalisasi diperlukan
seorang pemimpin yang mampu adaptif terhadap globalisasi itu sendiri, dan bersedia
mengedepankan kepentingan konsumen. Konsumen yang berhak untuk menentukan
barang mana yang akan mereka beli, termasuk konsumen yang bisa menentukan harga
barang yang hendak mereka beli. Pemimpin negara yang menegasikan pola-pola keinginan
konsumen, dianggap oleh Ohmae sebagai pemimpin yang tuli (deaf ears).8
Pokok gagasan kedua yang relevan dengan penelitian yang hendak dilakukan adalah,
konsepsi mengenai negara kawasan yang diajukan oleh Ohmae. Ia mencoba menjelaskan
mengenai kondisi perekonomian dunia pasca Perang Dingin, menurutnya, perkembangan
perekonomian di daerah atau negara bagian yang memiliki otonomi di suatu negara memiliki
kecenderungan lebih berhasil ketimbang dikelola secara sentralistis di pusat. Seperti yang
dicontohkannya dengan kasus yang terjadi di Cina, ternyata tingkat perekonomian daerah-
daerah otonom seperti Hongkong GNP per kapitanya kira-kira $12.000, Shenzen GNP per
kapitanya $5.695, dan Guangzhou meningkat lebih dari level $5.000. (bagi Cina secara
keseluruhan, gambaran yang bisa dibandingkan adalah $317). Dengan fakta ini, maka
Ohmae mengajukan suatu gagasan tentang perlunya membentuk zona-zona perekonomian
ini berdasarkan konsep negara kawasan, sebab menurutnya sudah terbukti jauh lebih
berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan warganya. Sebagaimana diungkapkannya “Di mana kesejahteraan eksis, ia berdasarkan wilayah. Dan ketika sebuah wilayah menjadi makmur, maka ke-beruntungannya yang baik akan melimpah ke wilayah-wilayah di sekitarnya baik di dalam maupun di luar federasi politis di mana ia menjadi bagiannya.” 9
Berangkat dari penjelasan pertama yang menyatakan bahwa negara haruslah berhenti
pada posisi fasilitator, Ohmae menawarkan satu konsepsi negera kawasan, atau yang dalam
istilahnya disebut sebagai natural economic zone. Dengan sistem ekonomi regional seperti
ini, diharapkan bisa menjamin pertumbuhan ekonomi yang adil di dalam satu kawasan.
Negara kawasan seperti yang dibayangkan oleh Ohmae adalah satu wilayah yang tersusun
7 Kenichi Ohmae, The End of the Nation-State: the Ries of Regional Economies. ( New York: Simon and Schuster Inc. , 1995). Ch.68 Faulks, op. cit. hal.57.9 Ohmae, op. cit, ch. 7
bab1-2 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 33 7/11/12 11:24 AM

34
oleh kekuatan-kekuatan pasar yang beroperasi baik di dalam atau di luar batas-batas negara
itu sendiri. Beberapa wilayah yang dicontohkannya berhasil menerapkan strategi ekonomi
seperti ini antara lain Region Shutoken di Jepang. Negara kawasan seperti Shutoken lebih
memiliki kecenderungan sebagai kawasan ekonomi ketimbang kawasan politik yang
sangat terbuka terhadap kepemilikan dan investasi asing (foreign ownership and foreign direct investment). Konsekuensi logis dari hal ini adalah negara yang dalam hal ini adalah
pemerintah pusat, mestilah menghadapi tantangan untuk mengembangakan satu struktur
koordi-nasi federal yang lebih fleksibel.10
Dalam konteks militer, konsep negara kawasan menurut Ohmae pada gilirannya juga
mendorong agar logika kemiliteran negara tidak lagi pada kontrol kawasan atau teritori.
Kontrol atau pengendalian teritorial menjadi semakin tidak relevan tatkala nilai-nilai
pengetahuan mengenai sumber daya alam dan kebebasan politik menjadi bagian penting
dari globalisasi ekonomi.11 Gagasan Ohmae mengenai penyingkiran logika penguasaan
teritorial oleh militer lahir dari satu kebutuhan akan pengurangan peran negara melalui
aparatusnya di lapangan, sementara masyarakat yang dibahasakan olehnya sebagai
konsumen harus diberikan keleluasaan untuk bisa menentukan pilihan-pilihan mereka
secara rasional tanpa harus ada unsur-unsur yang bisa membatasi pilihan mereka, termasuk
di dalamnya negara dan aparatus militernya.
2.3.
Keith Faulks: Mengembalikan Negara
Masih dengan dasar filosofis yang sama, globalisasi juga bisa dijelaskan sebagai
dampak dari kemampuan kapital untuk mencari daerah-daerah baru terlepas dari batas-
batas teritori kenegaraan maupun sekat-sekat identitas guna memperluas pasar. Keith
Faulks mendefinisikan globalisasi sebagai kemampuan satu idiologi politik untuk
mengkonstruksikan nilai-nilai pasar bebas. Sebagai hasil interaksi sosial antara negara
dan kelompok masyarakat – dalam hal ini Multinational Corporation (MNC) – globalisasi
ekonomi bukan hanya satu proses ekonomi yang tak terelakkan, melainkan di dalamnya
berisi pemikiran yang sangat kuat dari para pakar politik neo liberal yang didukung oleh
sekelompok politisi yang menaruh kecurigaan terlalu besar terhadap keinginan negara
untuk melakukan intervensi kepada masyarakat.12
10 Ibid. hal.100.11 Faulks op.cit.hal.58.12 Ibid.hal.71.
bab1-2 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 34 7/11/12 11:26 AM

35
Mengutip Hirst dan Thompson (1996) dalam Faulks (1999), globalisasi berbeda
dengan konsepsi internasionalisasi ekonomi. Jika dalam kurun waktu sangat panjang
internasionalisasi ekonomi telah terjadi di dunia, sementara globalisasi ekonomi adalah
perkembangan mutakhir dari kemampuan korporasi-korporasi besar dunia untuk
memperluas jangkauan pasar mereka. Perbedaan paling mencolok adalah tetap pada negara
sebagai entitas penting dalam konteks sistem ekonomi yang berlangsung. Internasionalisasi
ekonomi masih memberikan posisi yang penting kepada negara untuk mempengaruhi
keputusan-keputusan ekonomi politik yang dibuat, sementara globalisasi justru secara
sistematis menyingkirkan peran negara, untuk menggantinya dengan aktor-aktor pasar.13
Dalam konteks ini, aktivitas ekonomi yang massif dalam proyek globalisasi telah bergerak
melampaui kemampuan negara untuk mengatur itu semua. Dan dampak yang tidak bisa
dipungkiri adalah adanya ketimpangan yang sangat jelas antara negara-negara maju
dengan negara-negara berkembang. Globalisasi dan jargon pasar bebasnya bukan hanya
tidak mampu mengatasi problem ketimpangan yang sangat mendasar ini, melainkan
juga dicurigai oleh Faulks justru melanggengkan problem ketimpangan antar negara itu
sendiri, karena kepentingan negara-negara maju cenderung dominan dalam setiap agenda
global yang dimunculkan ke permukaan. Dengan ungkapan yang lebih ekstrim, Faulks
menyatakan bahwa globalisasi ekonomi lebih tepat dikatakan sebagai polarisasi ekonomi
(1995:64).
Selanjutnya, Faulks banyak mengkritik istilah-istilah yang sering mucul dalam konteks
globalisasi, di antaranya mengembalikan istilah Multinational Corporation ketimbang
Transnational Corporation (TNC), kemudian istilah globalisasi lebih baik digantikan dengan
internasionalisasi. Dari perdebatan yang alot di antara para pemikir globalisasi, Faulks
mengambil tiga kesimpulan yang mendasari pemikiran lanjutnya mengenai globalisasi,
yakni: pertama, globalisasi yang konon melahirkan budaya global, di mana nilai-nilai yang
diterima secara universal adalah nilai-nilai barat yang tersosialisasikan secara massif melalui
perangkat teknologi informasi yang semakin canggih dan melampaui batas-batas negara,
ternyata tidak juga mampu menggeser nilai-nilai serta praktik-praktik masyarakat yang lahir
dari identitas kelokalan mereka seperti suku, agama dan kearifan lokal. Bahkan di sebagian
wilayah, praktik-praktik itu semakin mampu menyedot perhatian individu dan masyarakat
di belahan dunia manapun. Dengan kata lain, yang lokal tidak senantiasa tergantikan oleh
yang global sebagai konsekuensi dari globalisasi itu sendiri. Kedua, dalam konteks sistem
13 Ibid.hal.62.
bab1-2 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 35 7/11/12 11:26 AM

36
ekonomi dunia, ada baiknya kita lebih memilih internasionalisasi ekonomi ketimbang globalisasi ekonomi, karena konsekuensi dari terminologi globalisasi ekonomi adalah aktor-aktor ekonomi tidak terikat oleh negara. Padahal seperti kita ketahui bahwa fluktuasi eko- nomi internasional yang diakibatkan oleh perilaku para aktor-aktor ekonomi dalam pasar keuangan sangat berhubungan erat dengan stabilitas negara. Artinya aktor ekonomi sebenarnya cukup menentukan tingkat stabilitas suatu negara. Jika demikian halnya, melepaskan aktor-aktor ekonomi dari jangkauan negara, sama saja dengan melepaskan kontrol atas faktor instabilitas yang memiliki potensi untuk mengganggu negara. Ketiga, besarnya peranan negara dalam perusahaan-perusahaan besar yang mengaku korporasi transnasional (TNC), padahal sesungguhnya mereka adalah korporasi multinasional (MNC) menunjukkan bahwa agenda politik dan hukum suatu negaralah yang menjadi rujukan dasar bagi korporasi-korporasi itu untuk mengembangkan sayap bisnis dan manajemen mereka.
Dari ketiga hal tersebut, Faulks mencoba mengingatkan kita bahwa globalisasi adalah hasil dari interaksi yang rumit dan lama antara negara dan korporasi multinasional. Sehingga pada dasarnya, baik individu maupun asosiasi di masyarakat sesungguhnya masih membutuhkan negara, karena negara memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh aktor lain seperti korporasi dan masyarakat, yakni menguasai dan memegang kekuatan militer, kemudian kekuasaan komunikasi dan ekonomi (1995:69).
Singkatnya, bagi Faulks, globalisasi adalah neo liberalisasi. Bagi kaum neo liberal, keberadaan negara menjadi paradoks, di satu sisi mereka kritis terhadap negara, tetapi di sisi yang lain mereka menempatkannya sebagai the necessary evil (1999:71).14
Dalam konteks militer, Faulks tidak secara eksplisit menyoroti peranan militer dalam kancah globalisasi, namun berdasar pandangannya atas globalisasi itu sendiri, kiranya Faulks menganggap militer adalah faktor unik yang hanya dimiliki oleh negara, sehingga hal tersebut tidak mungkin tergantikan ataupun digantikan dengan institusi di luar negara. Artinya, berbicara militer, sudah pasti tidak terlepas dari diskursus mengenai negara. Mengidentifikasi globalisasi dalam ranah militer, berarti juga berbicara pengaruh globalisasi di dalam negara. Konsepsi ini sekaligus mengkritik secara keras pandangan yang menyatakan berakhirnya konsep negara bangsa, hal itu tidak lain hanya rumor yang dibesar-besarkan (1995:213). Negara tetap merupakan entitas dengan kekuatan yang sangat besar yang memiliki kemungkinan untuk menjalankan kepentingan dan tujuan masyarakat.
14 Terminologi the necessary evil dituangkan oleh Faulks untuk menyebutkan bagaimana sesungguhnya kaum liberal memposisikan negara dalam dua cara pandang yang seringkali bertolak belakang. Di satu sisi mereka memandang bahwa intervensi negara kepada masyarakat sipil haruslah dibatasi sedemikian rupa, tetapi juga sekaligus menginginkan agar negara bisa menjamin keamanan masyarakat sipil dari bentuk-bentuk ancaman dari luar.
bab1-2 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 36 7/10/12 1:55 PM

37
2.4. Jonathan Krishner dan Persoalan National Security
Jonathan Krishner dalam Globalization and National Security mengungkapkan pertanyaan kunci dari perdebatan mutakhir mengenai pertanyaan, apakah konsekuensi globalisasi bagi keamanan nasional itu sendiri. Bagi Krishner, globalisasi adalah soal berubahnya apa yang ia namakan sebagai nature of the game yang dalam bahasa Indonesianya kurang lebih adalah aturan main. Hal ini tidak terkait dengan apakah satu negara tetap mempertahankan konsep traditional state-centric ataupun negara tersebut justru mengadopsi paradigma multistate-centric, atau ketika tujuan-tujuan nasional yang dirumuskan oleh negara tersebut tetap sama dan tidak berubah, globalisasi pasti menuntut adanya cara-cara baru dalam memperhitungkan bentuk-bentuk tantangan serta ancaman bukan hanya yang datang dari luar negara, melainkan juga tantangan serta ancaman yang berasal dari dalam negeri. Kegagalan dalam memperhitungkan dampak-dampak globalisasi itu akan berakibat pada pemahaman yang kurang tepat atas perubahan-perubahan keseimbangan kekuatan, prospek peperangan dan pilihan-pilihan strategis yang dihadapi oleh negara.15
Dalam pandangan Krishner di atas, jelas, globalisasi dianggap sebagai satu faktor pendorong yang sifatnya kurang lebih independen terhadap negara-negara itu sendiri. Globalisasi memiliki kemampuan yang memaksa semua pihak untuk menyesuaikan diri dengan aturan-aturan baru yang lahir dari proses interaksi masyarakat global. Kemampuan negara-negara dalam menyerap norma-norma universal dari dinamika interaksi global menjadi alat paling ampuh untuk memaknai lebih jauh globalisasi yang pada gilirannya menentukan dengan tepat tindakan nasional ataupun strategi nasional yang hendak dilakukan dalam mencapai tujuan-tujuan nasional suatu negara.
Secara sosiologis, tentu saja globalisasi dalam kacamata Krishner dapat dilihat sebagai satu struktur yang mendorong negara – sebagai agen – untuk melakukan tindakan. Sementara para agen sendiri – yang dalam hal ini dilihat sebagai negara – menjadi pihak yang berada pada posisi subordinat dari kekuasaan dan aturan global itu.
Selanjutnya Krishner juga menjelaskan mengenai apa yang dimaksud sebagai keamanan nasional itu sendiri. Dia mengemukakan bahwa keamanan nasional merujuk pada kekerasan politik yang terorganisasi yang merupakan ungkapan dari kepentingan vital oleh paling tidak satu negara. Dalam pada ini, konsekuensi dari globalisasi bagi keamanan nasional menurut Krishner, bagaimanapun tidak lagi bisa dibatasi hanya pada persoalan
15 Jonathan Krisner dalam “Globalization and National Security” (New York, Routledge,2006) hal.1
bab1-2 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 37 7/10/12 1:55 PM

Sumber: Jonathan Kirshner, 2006
Globalization
Autonomy andState Capacity
Balance of Power Axes of Conflict
38
perang ataupun pemberontakan serta kekacauan. Konsekuensi itu juga meliputi bagaimana
globalisasi juga mengakibatkan perubahan keseimbangan kekuatan, baik keseimbangan
kekuatan pertahanan dan penyerangan suatu negara maupun perubahan pada faktor-faktor
lain yang bisa memunculkan dilema keamanan, kemungkinan-kemungkinan terjadinya
perang dan perubahan keandalan suatu negara untuk mempertahankan kepentingan
nasionalnya.16
Sekali lagi penjelasan ini mencoba menghubungkan keterkaitan antara globalisasi
dan militer melalui terminologi keamanan nasional. Pada titik ini kita bisa melihat
bahwa kepentingan nasional sesungguhnya menjadi faktor pendorong yang cukup kuat
bagi negara-negara di dunia untuk membangun kekuatan militernya. Hanya saja dalam
konteks kekinian ketika pola-pola ancaman terhadap keamanan nasional sebagian besar
telah bertransformasi karena gelombang besar perubahan sosial di masyarakat, termasuk
di dalamnya akibat revolusi industri dan ekspansi dramatis (menggunakan terminologi
Kirshner) dari teknologi komunikasi dan informasi, muncul pemahaman-pemahaman
baru mengenai keamanan yang memang pada gilirannya lahir dari perkembangan konsep
keamanan nasional itu sendiri.
Lebih jauh penjelasan mengenai hal ini digambarkan secara sistematis oleh Kirshner
melalui gambar di bawah ini, yang menjelaskan bagaimana globalisasi mendorong
terjadinya perubahan-perubahan mendasar pada tiga hal terkait keamanan nasional, yakni:
otonomi dan kapasitas negara, keseimbangan kekuatan dan kealamiahan konflik.
Gambar 1. Arah Perubahan Globalisasi
16 Ibid hal.2.
bab1-2 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 38 7/11/12 11:26 AM

39
1. Otonomi dan Kapasitas Negara. Yang paling nyata dari konsekuensi globalisasi adalah melemahnya kekuatan dan kedaulatan suatu negara. Meskipun hal ini masih bisa diperdebatkan karena dalam beberapa sisi globalisasi justru bisa menjadi alat yang efektif untuk berlangsungnya satu proses transformasi dalam satu masyarakat. Namun, fakta bahwa telah terjadi penurunan kemampuan suatu negara dalam mengelola ekonomi makronya mengakibatkan negara mengalami kesulitan untuk melakukan upaya-upaya menggerakkan sumber daya yang mereka miliki demi tujuan perang melalui mobilisasi kapital. Selain itu, banjirnya teknologi komunikasi dan informasi baru yang semakin canggih menyebabkan kondisi hypermedia environment yang cukup menyulitkan negara untuk mengontrol masyarakatnya. Memang, bagi sebagian kalangan menilai bahwa kemajuan teknologi seperti ini tidak bisa secara total dikatakan melemahkan negara, namun justru memberikan kesempatan kepada negara itu untuk melakukan transformasi dan menguatkan masyarakatnya. Dengan mengutip apa yang dikatakan oleh Ronald Deibert, Kirshner (2006) menyatakan bahwa kenyataan seperti itu telah mengakibatkan perubahan terhadap kekuasaan relatif dari kekuatan sosial. Hal ini karena kekuatan sosial yang kepentingan-kepentingannya cocok dengan lingkungan komunikasi seperti itu akan menjadi tertolong ketimbang kekuatan sosial yang tidak cocok dengan situasi yang lebih terbuka itu.
2. Penyeimbangan Kekuatan. Perubahan yang begitu besar dan cepat dari teknologi komunikasi dan informasi pada gilirannya tidak hanya mendorong perubahan kekuatan sosial, melainkan juga mengakibatkan perubahan pada kekuasaan relatif dari kekuatan negara. Tidak bisa dipungkiri, dengan terbukanya akses informasi, hal itu mendorong negara-negara yang semula melakukan kontrol yang kuat terhadap rakyatnya, terpaksa membuka diri terhadap perubahan. Kondisi ini kemudian justru menguntungkan munculnya kekuatan politik yang lebih liberal di negara tersebut. Atau justru, kebijakan-kebijakan politik negara tersebut secara perlahan mulai berkompromi dengan keterbukaan. Globalisasi juga pada gilirannya mempengaruhi pola-pola hubu-ngan antara negara dan pasar (perdagangan dan produksi). Secara ekonomi, negara-negara yang tidak siap menghadapi liberalisasi ekonomi akan berada di sudut ketimbang negara-negara yang telah siap dengan strategi-strategi untuk menghadapi liberalisasi ekonomi. Dengan kecanggihan teknologi informasi
bab1-2 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 39 7/10/12 1:55 PM

40
seperti sekarang ini, orang bisa setiap saat membandingkan kekuatan ekonomi dari masing-masing negara, sehingga setiap saat pula bisa dihitung secara relatif kekuatan politik satu negara jika dibandingkan dengan negara lainnya.
3. Kealamiahan Konflik. Globalisasi juga mempertajam bentuk, gaya dan pola kekerasan politik yang terorganisasi karena kekuatan globalisasi justru cenderung membuat instabilitas di suatu negara atau kawasan. Dinamika sosial yang begitu cepat mendorong bentuk-bentuk konflik menjadi semakin spesifik karena nilai-nilai global yang disebarkan pada gilirannya mesti berhadapan dengan norma-norma lokal di masyarakat. Jika kondisi ini tidak bisa dikelola maka konflik bisa senantiasa muncul di dalam masyarakat. Selain itu globalisasi juga mengakibatkan perubahan terhadap ekspresi kekerasan dan peperangan. Contoh paling nyata yang paling sering disebutkan adalah adanya gerakan perlawanan terhadap dominasi AS melalui gerakan terorisme yang menggunakan label agama tertentu. Kemungkinan terjadinya perang juga semakin terbuka dengan dorongan kuat globalisasi. Alasan-alasan yang semula terasa janggal untuk melakukan perang, saat ini justru sering digunakan, seperti demokratisasi dan kemanusiaan. Pada intinya, globalisasi cenderung melemahkan negara yang lemah, dan bisa memperkuat negara yang memang sudah kuat.
2.5.
Studi Empirik Norin Ripsman dan T.V. Paul
Secara gamblang Ripsman dan Paul mengklasifikasikan para sarjana yang berbicara mengenai globalisasi serta hubungannya dengan keamanan nasional dan militer menjadi tujuh kelompok, di antaranya:
1. Kelompok sarjana globalisasi aliran keras (hardcore globalization scholar) diwakili oleh Kenichi Ohmae yang menjelaskan bagaimana globalisasi ekonomi telah menyebabkan fokus negara pada isu keamanan nasional semakin berkurang, termasuk ancaman-ancaman proliferasi pada gilirannya tidak lagi cukup diatasi oleh kekuatan militer satu negara. Hal ini terutama didorong oleh keberadaan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan World Bank yang dari segi structural adjustment yang mereka berikan pada negara-negara kreditur, mensyaratkan pengurangan pembelanjaan sektor militer, ka-
bab1-2 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 40 7/10/12 1:55 PM

41
rena mereka memandang biaya yang digunakan untuk perang, seringkali tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh dari perang tersebut (2010:24).
2. Kelompok sarjana pemikir globalisasi aliran halus (soft globalization scholar) diwakili oleh Jonathan Kirshner yang menyatakan tidak jauh berbeda dengan aliran sebelumnya (hardcore), bahwa globalisasi telah menjadi satu mesin pendorong yang sangat kuat bagi perubahan sosial, ekonomi, politik di dalam negara. Selain itu, batas-batas negara juga menjadi lebih rapuh dari sebelumnya. Oleh karena itu, peran militer dalam menjaga keamanan nasional cenderung berubah dan semakin memudar karena tekanan pengaruh global terhadap perubahan masyarakat di satu negara (2010:25).
3. Kelompok sarjana pemikir globalisasi tradisi liberalisme komersial (comercial liberal tradition scholar) diwakili oleh Richard Rosecrance yang menyatakan bahwa perdagangan lebih penting ketimbang kekuatan militer. Oleh karena-nya, di masa depan, negara harus mengurangi hasrat-hasrat penyelesaian persoalan ataupun konflik dengan jalan peperangan, bahkan apabila hal itu melibatkan persoalan teritorial sekalipun (2010:26).
4. Kelompok sarjana pendukung demokrasi perdamaian (democratic peace scholar) yang menyatakan bahwa semakin banyaknya negara-negara yang mengadopsi nilai-nilai demokrasi dalam sistem politiknya, hal itu akan secara langsung mengurangi konflik dalam bentuk peperangan. Hal ini dikarenakan, dalam negara-negara yang demokratis, keputusan untuk melakukan perang atau tidak, harus mendapat persetujuan publik dan parlemen. Dengan adanya proses seperti ini, maka hasrat perang yang mungkin muncul dari negara, secara otomatis akan termoderasi dengan pandangan-pandangan yang mungkin muncul dari aktor-aktor di luar negara (2010:27).
5. Kelompok sarjana pendukung aliran normatif (normative school) diwakili oleh Mark Zacher yang menyatakan bahwa, di era sekarang ketika banyak muncul norma-norma global yang kemudian diserap oleh banyak negara seperti hak asasi manusia, anti genosida, intervensi kemanusiaan, integritas kawasan, kedaulatan negara dan perlawanan terhadap penjahat perang. Hal ini telah membuat keputusan untuk melakukan peperangan semakin sulit karena secara normatif perang bukan satu pilihan yang secara mudah dicarikan alasannya sehingga tentu saja mengurangi secara drastis peran militer dalam menjaga satu kawasan (2010:28).
bab1-2 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 41 7/10/12 1:55 PM

42
6. Kelompok aktivis pendukung gerakan kultur global, menyatakan bahwa globalisasi kebudayaan akan mengurangi konflik internasional. Hal ini bisa terjadi karena dengan budaya global yang ada, masyarakat bisa menikmati sajian-sajian kebudayan yang sama di seluruh penjuru dunia, seperti musik, film, buku, informasi dan banyak lainnya yang menurut mereka jauh lebih bisa memberikan energi pemersatu ketimbang energi pembelah masyarakat (2010:28).
7. Kelompok yang terakhir menyatakan bahwa, dengan adanya globalisasi sekarang ini, meski yang disebut budaya global itu semakin meluas jangkauan sosialisasinya, tetapi di sisi lain terjadi semacam penguatan atas rasa identitas agama dan budaya di tingkat lokal. Penguatan ini terkadang justru mengarah pada bentuk-bentuk tindakan kekerasan seperti halnya terorisme yang secara “pintar” memanfaatkan teknologi informasi yang menjadi motor paling berpe-ngaruh dari globalisasi itu sendiri (2010:28).
Dalam cara pandang yang agak berbeda, Ripsman dan Paul yang telah melakukan satu penyelidikan empiris terkait bagaimana globalisasi berimbas pada keamanan nasional negara-negara yang ada di dunia menyebutkan beberapa proposisi awal yang tidak terbukti kebenarannya terkait dengan globalisasi dan keamanan nasional. Salah satunya adalah bahwa globalisasi tidak serta merta merubah pola relasi global yang tengah dan sedang berlangsung selama beberapa kurun waktu, hal yang paling mencolok pasca Perang Dingin justru globalisasi telah mengakibatkan pola penyerangan teroris yang semakin acak dan canggih, plus perang terhadap gerakan itu sendiri yang semakin melibatkan banyak negara di dunia. Secara skeptis mereka menyatakan bahwa pengaruh globalisasi terhadap keamanan nasional pasca Perang Dingin hanyalah bagaimana negara-negara di dunia secara bersama-sama memerangi terorisme yang dianggap sebagai new public enemy. Pada tataran negara sendiri, apa yang disebut sebagai gelombang Revolutionary in Military Affairs (RMA) tidak senantiasa terbukti atau sejalan dengan nilai-nilai yang dibawa oleh gagasan tersebut. Justru dalam banyak hal, negara-negara di dunia masih banyak yang memperkuat diri dengan senjata pemusnah massal seperti nuklir dan penambahan secara signifikan kekuatan personil militernya. Meski transformasi dalam RMA mensyaratkan beberapa hal, terkait dengan efisiensi dalam peperangan, pada kenyataannya penguatan infrastruktur militer nasional tetap menjadi belanja yang cukup besar bagi negara-negara di dunia. Kekuatan militer yang semakin besar adalah salah satu hal yang harus mereka siapkan dalam rangka
bab1-2 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 42 7/10/12 1:55 PM

43
menghadapi bentuk-bentuk ancaman yang muncul baik dari dalam maupun dari luar negeri.
Ada beberapa proposisi yang menurut mereka layak untuk diuji kebenarannya karena saat ini proposisi itu seperti telah menjadi semacam keyakinan di kalangan para sarjana globalisasi yang menekuni persoalan-persoalan keamanan nasional. Proposisi itu dibagi ke dalam dua level, yakni proposisi yang harus diuji pada level global (PG) dan pada level negara (PS). Pengklasifikasian itu didasari oleh adanya pemahaman dari beberapa sarjana yang mengatakan bahwa globalisasi telah mendorong terjadinya perubahan-perubahan yang sangat mendasar dalam pola hubungan internasional, di sini proposisi level global yang diuji antara lain: (PG1) Menurunnya tingkat konflik antar negara di dunia; (PG2) Penurunan belanja pertahanan dunia dan berkurangnya jumlah tentara di dunia; (PG3) Peningkatan peran serta Institusi global ataupun institusi regional multilateral dalam hal keamanan; (PG4) Peningkatan secara dramatis insiden terorisme global. Keempat proposisi tersebut akan diuji untuk melihat sejauh mana perubahan terjadi pada level global, meski bisa saja perubahan itu disebabkan oleh globalisasi yang menggejala ataupun memang itu adalah persoalan yang terjadi sejak lama.
Dengan asumsi bahwa globalisasi juga memiliki dampak yang tidak kecil pada level negara, mereka sebaliknya juga mengajukan beberapa proposisi-proposisi umum yang hendak diuji untuk melihat sejauh mana perubahan di level negara itu berlangsung, proposisi itu antara lain: (PS1) Pergeseran paradigma peperangan dari peperangan antar negara versi Clausewitzian menuju peperangan jenis ketiga – perang etnis sipil dan perang antar negara kecil; (PS2) Pergeseran perhatian keamanan nasional ne-gara-negara di dunia akan tantangan peperangan post industry – utamanya terorisme; (PS3) Kebijakan keamanan nasional semakin merambah wilayah-wilayah yang secara tradisional berada di luar persoalan pertahanan seperti perdagangan, ekologi, migrasi dan kesehatan dikarenakan meningkatnya ancaman ekonomi, lingkungan dan bibit penyakit; (PS4) Perubahan doktrin militer nasional dari yang semula mengedepankan penyerangan menjadi pertahanan ataupun pencegahan; (PS5) Peningkatan negara-negara di dunia yang lebih memilih menggunakan pendekatan soft balancing untuk menghadapi rival tangguh mereka ketimbang pendekatan tradisional dengan menggunakan hard balancing; (PS6) Penurunan angka wajib militer dan jumlah tentara di suatu negara; (PS7) Penurunan belanja militer negara; (PS8) Pergeseran paradigma perkembangan militer dari prajurit perang menjadi pasukan perdamaian; (PS9)
bab1-2 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 43 7/10/12 1:55 PM

44
Privatisasi layanan keamanan oleh negara dengan melibatkan aktor non negara dalam kegiatan pertahanan; (PS10) Peningkatan upaya negara dalam memperjuangkan keamanan negaranya melalui organisasi atau forum regional.
Penelitian ini sendiri dilakukan pada negara-negara di dunia dengan mengklasifikasikannya menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok kekuatan utama dunia (AS, Rusia, dan Cina), negara-negara yang berada di kawasan yang relatif stabil (Eropa, Asia Tenggara dan Amerika Latin), negara-negara yang berada di kawasan yang penuh dengan ketegangan (Asia Selatan, Timur Tengah dan Asia Timur) serta yang terakhir negara-negara yang tergolong negara lemah dan mungkin hampir gagal (Afrika).
Dari hasil penelitian tersebut, ada beberapa kesimpulan yang bisa mereka berikan sebagai satu upaya untuk menguji seberapa nyata proposisi tersebut dalam realitas ekonomi politik di dunia saat ini. Pertama, meskipun terjadi penurunan eskalasi perang antar negara (PG1) namun intensitas konflik antar negara tidak menunjukkan ke-cenderungan yang sama. Sebaliknya konflik antar negara semakin meningkat meskipun tidak berujung pada terjadinya perang. Sementara itu terkait belanja pertahanan dunia, ada kecenderungan menurun namun hanya sampai tahun 1998. Setelah itu, memasuki tahun 1999 terjadi kecenderungan belanja pertahanan terus menaik dan melonjak pasca tragedi 11 September 2001 sampai sekarang. Di sini terjadi paradoks, meskipun jumlah tentara menurun, namun pembelanjaan militer, terutama dalam pembelian dan pengadaan senjata terus mengalami kenaikan, sehingga ada problematika di (PG2). Untuk peran serta institusi regional maupun global dalam hal keamanan (PG3), hasil penelitian mereka menyimpulkan bahwa memang betul terjadi pertumbuhan yang luar
Tabel 1. Analisis Proposi pada Level Negara dan Global
bab1-2 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 44 7/10/12 1:55 PM

45
biasa dari organisasi-organisasi internasional maupun regional, bak cendawan di musim hujan, mereka tumbuh seiring era keterbukaan pasca Perang Dingin. Namun demikian bahwasanya mereka mampu secara institusional mempengaruhi keputusan-keputusan nasional maupun internasional dalam hal menjaga keamanan, sepertinya belum bisa disandingkan dengan peran vital negara dalam hal ini. Oleh karenanya, ada kontradiksi dalam (PG3). Sedangkan mengenai proposisi level global yang terakhir (PG4), mereka menyimpulkan bahwa benar terjadi peningkatan insiden terorisme, terutama pasca 11 September 2001, di mana terorisme lekat dengan pelabelan terhadap gerakan Islam radikal. Meskipun begitu, situasi ini menunjukkan adanya perbedaan ketimbang terorisme yang terjadi sebelum 11 September 2001 yang didominasi oleh perlawanan terhadap satu negara seperti halnya yang terjadi di Inggris Raya dengan IRA-nya, kemudian perlawanan Kelompok Basque di Spanyol. Kendati tindakan terorisme lintas negara mengalami peningkatan yang sangat signifikan, hal itu menurut mereka tidak bisa dikatakan menumbangkan negara, artinya mereka membenarkan proposisi global yang terakhir.
Setelah analisis pada level global dilakukan, Ripsman dan Paul kemudian menguji proposisi yang diasumsikan berlangsung di level negara, hasil dari analisis mereka menunjukkan beberapa kecenderungan yang berbeda di antara kelompok negara- negara yang telah mereka klasifikasikan sebelumnya (kekuatan utama dunia, kawasan stabil, kawasan bergejolak dan negara-negara lemah atau gagal). Berikut tabel yang mereka jelaskan untuk menggambarkan bagaimana kondisi proposisi tersebut:
bab1-2 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 45 7/10/12 1:55 PM

Sumber: Globalization and National Security State (2010) Ripsman and Paul-166
46
Berdasarkan analisis yang telah mereka lakukan, ada 2 kesimpulan kecil yang pada akhir tulisan mereka diajukan sebagai satu fakta empirik dari proposisi yang telah mereka uji. Pertama, mereka menekankan bahwa gagasan yang menyatakan bahwa globalisasi akan meruntuhkan negara bangsa ataupun peran negara terutama dalam hal menciptakan keamanan bagi warga dunia adalah tidak benar karena mereka menegasikan satu kekuatan pokok negara sebagai institusi sosial ekonomi yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan tantangan global. Kedua, berdasarkan penjelasan di atas, meskipun tantangan dan ancaman global yang muncul ketika institusi negara ini berhubungan dengan sistem pasar liberal maupun kesepakatan-kesepakatan
bab1-2 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 46 7/10/12 1:55 PM

47
multilateral yang mensyaratkan banyak hal maupun nilai-nilai yang sebelumnya tidak mereka lakukan, masing-masing negara memiliki kemampuan untuk melakukan adaptasi sesuai dengan apa yang menjadi kepentingan nasional mereka sebagai sebuah negara bangsa. Sekali lagi mereka menekankan bahwa negara adalah institusi yang tidak hanya adaptif, tetapi juga memiliki daya lentur yang sangat kuat untuk bernegosiasi dengan tantangan global itu sendiri. Dengan kata lain, meski pengaruh kekuatan global tidak bisa dipungkiri cukup terasa bagi setiap negara, namun globalisasi tidak juga serta merta mampu menegasikan peran negara dalam kancah hubungan internasional termasuk dalam mengupayakan keamanan bagi warganya.
bab1-2 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 47 7/10/12 1:55 PM

48
Selain dari kesimpulan tersebut, Ripsman dan Paul juga memberikan sumbangan teoritik bagi para sarjana yang menekuni masalah globalisasi dengan menyatakan bahwa tidak satupun para pemikir globalisasi yang bisa secara utuh menangkap fenomena global yang terjadi sekarang (2010:177). Menurutnya, para pemikir liberal gagal menangkap kemampuan negara untuk tidak juga meninggalkan pendekatan kalkulasi keamanan tradisional, sementara itu para pemikir realis meski pada kenyataannya keberadaan negara masih tetap kuat, mereka juga tidak bisa menangkap realita bahwa banyak negara yang berada di kawasan yang stabil pada kenyataannya jauh mendapatkan manfaat dalam hal pengelolaan keamanan nasionalnya ketimbang ka-wasan yang penuh gejolak. Hal ini telah mendorong negara-negara di dunia untuk mem- bangun satu organisasi regional yang bisa berbagi tanggung jawab di antara anggota-anggotanya dalam menjawab tantangan yang mungkin muncul mengganggu keamanan nasionalnya, kenyataan ini sesungguhnya mencerminkan satu perpindahan paradigma keamanan nasional dari dunia realis.
Ripsman dan Paul juga mengkritik kegagalan kaum konstruktivis dalam melihat praktik-praktik keamanan (yang menurut kaum konstruktivis sebagai tradisional) masih dijalankan oleh sebagian besar negara, terutama yang berada di kawasan yang bergejolak. Kenyataan bahwa tidak selamanya norma-norma global seperti hak asasi manusia atau demokratisasi ditempatkan di atas segala-galanya, karena pada banyak negara, persoalan itu dianggap tidak sepenting keamanan nasional mereka.
Oleh karenanya, mereka berdua kemudian menawarkan kepada khalayak untuk membangun satu pendekatan baru yang terlepas dari paradigma mainstream yang telah ada dan diyakini oleh sebagian besar sarjana di dunia. Masih menurut mereka, dalam melihat gejala globalisasi dan keamanan nasional, penting untuk lebih banyak memasukkan nuansa dan pendekatan yang lebih eklektis sehingga kita mampu membaca segala macam kemungkinan yang bisa timbul akibat pengaruh global.
2.6.
Rangkuman
Varian pemikiran yang muncul dan lahir seputar globalisasi dan keamanan nasional adalah hasil dari interaksi yang intens antara para sarjana dengan isu-isu seputar keamanan nasional dan dinamika hubungan internasional global. Pun demikian, sebenarnya, secara genealogis kita bisa melihat kelahiran pemikiran-pemikiran tersebut tidak terlepas dari posisi para sarjana dalam peta diskursus pemikiran sosial.
bab1-2 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 48 7/10/12 1:55 PM

49
Ada sebagian yang berada di barisan yang memang menganjurkan satu tata dunia yang berlandaskan kepada kebebasan individu atau yang lebih kita kenal dengan tradisi liberalisme yang dalam beberapa hal menempatkan kekuatan ekonomi pasar sebagai mekanisme yang paling efisien untuk menciptakan kesejahteraan nasional dengan memberikan seminimal mungkin peran negara dalam membuat regulasi perekonomian seperti Kenichi Ohmae. Sementara itu, lawan kuat dari tradisi ini adalah mereka yang percaya bahwa mekanisme pasar untuk menciptakan kesejahteraan tidak lebih dari ilusi yang justru dibuat oleh kelompok kapitalisme multinasional untuk lebih menguatkan posisi mereka di dunia, sehingga agenda kesejahteraan tersebut sesungguhnya tidak akan pernah tercapai karena meniadakan satu hal yang paling esensial, yakni keadilan seperti Keith Faulks. Sisanya adalah mereka yang mencoba mencari jalan tengah atau tidak mau terjebak pada dua tradisi besar tersebut meskipun jika ditelaah lebih dalam lagi, seringkali mereka gagal untuk bisa membebaskan diri dari dua tradisi pemikiran itu. Dalam konteks buku ini, dicontohkan dengan Giddens dan Krishner, sedangkan Ripsman dan Paul lebih menekankan pada dimensi eklektis globalisasi itu sendiri.
Sementara itu, dari sisi kajian sosiologi militer, diperoleh gambaran bahwa sosiologi militer merupakan satu frasa yang sesungguhnya menggambarkan satu ranah kajian sosiologi dalam dunia militer, atau bisa juga dikatakan melihat militer dari sudut pandang sosiologis. Dalam konteks ini, melihat militer secara sosiologis tentu saja sangat tergantung dari pendekatan apa yang akan kita gunakan dalam melihat institusi militer itu sendiri atau subyek kajian apa yang menarik seseorang untuk membedah institusi militer. Contohnya, kita bisa saja membedah institusi militer dari perspektif teori gender dengan subyek kajian, bagaimana jenis kelamin laki-laki begitu dominan di dalam tubuh militer sehingga tubuh institusi militer mencerminkan pemikiran kaum laki-laki. Atau barangkali ada yang berminat untuk melihat sejauh mana perkembangan teknologi sebagai alat modernisasi kelembagaan mempengaruhi pola perilaku ataupun tindakan para prajurit atau perwiranya. Begitu seterusnya, sehingga sesungguhnya secara sosiologis, banyak hal yang masih bisa kita telaah dari institusi militer itu sendiri. Sementara untuk keperluan penulisan buku ini sendiri, perspektif sosiologi politik globalisasi akan digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh globalisasi ke dalam tubuh militer, khususnya Indonesia, serta sebaliknya, sejauh mana institusi militer Indonesia berkontribusi dalam kerangka membangun nilai-nilai universal dalam dunia militer.
Dari sisi sosiologi militer, apa yang dikemukakan oleh Eric, serta contoh-contoh studi sosiologi militer yang dituangkan dalam catatan Caforio menunjukkan bagaimana
bab1-2 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 49 7/10/12 1:55 PM

Diolah dari berbagai sumber
50
dalam perkembangan ranah studi ini, hasrat untuk bisa menelaah lebih jauh persoalan militer dari sudut pandang sosiologik mengarah pada dua kecenderungan besar. Pertama adalah mereka yang melihat dalam perspektif sosiologi politik, bahwa relasi antara militer dengan institusi sipil adalah jantung dari dinamika di dalam institusi militer itu sendiri. Dengan tesis yang sedemikian, penelaahan dan pembongkaran lebih jauh atas relasi ini dianggap sebagai satu mekanisme yang efektif untuk mendorong proses transformasi di dalam tubuh militer. Artinya, militer sebagai sebuah struktur sosial yang cenderung memiliki hasrat untuk mendominasi praktik-praktik sosial, terutama di negara yang sedang berkembang, hanya bisa direformasi jika elemen-elemen kekuasaan yang melingkupi dirinya dilepaskan dan dikembalikan kepada institusi sipil, termasuk kontrol terhadap institusi militer tersebut. Tesis ini, secara klasik berangkat dari pertanyaan Plato 2500 tahun yang lalu dalam Republic, mengenai who guards the guardian? Secara ringkas, kita bisa katakan bahwa perspektif seperti ini, sampai detik ini masih menjadi cara pandang yang dominan dalam melihat institusi militer secara sosiologik.
Sementara itu, pendekatan yang kedua adalah mereka yang mencoba keluar dari perspektif sebelumnya. Yakni dengan mengupayakan cara pandang membedah secara
Tabel 2. Pemetaan Teoritik Pemikiran Globalisasi
bab1-2 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 50 7/10/12 1:55 PM

51
mendalam praktik-praktik sosial di dalam institusi militernya sendiri. Kendati mereka tetap memasukkan faktor relasi antara militer dengan sipil, tetapi lebih jauh dari itu, cara pandang ini mencoba melengkapi cara pandang sebelumnya, bahwa militer pun suatu institusi sosial. Yang artinya kita layak membedah institusi militer dengan pisau-pisau analisis yang sering kita gunakan untuk membedah institusi sosial pada umumnya. Menurut saya, cara pandang ini melampaui persoalan relasi sipil dengan militer. Sebuah ikhtiar para sarjana untuk bisa menemukan jejak-jejak sipil di dalam tubuh militer.
Bagi Indonesia, beragamnya cara pandang dalam memaknai globalisasi mesti dilihat sebagai sebuah konteks pluralitas yang harus dipahami dan dimengerti oleh masyarakat dan negara. Kendati begitu, pada satu titik kita tetap harus menentukan pada cara pandang seperti apa Indonesia harus melihat dan memaknai globalisasi, pilihannya bisa mengikuti alternatif-alternatif yang ada, atau justru membangun satu tradisi baru dalam membaca dan memaknai globalisasi itu sendiri.
bab1-2 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 51 7/10/12 1:55 PM

52
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 52 7/10/12 2:11 PM

Bab III
Globalisasi dan Revolutionary in Military Affairs• Globalisasi dan Keamanan Nasional• Perkembangan Pemikiran Revolutionary in Military Affairs• Belanja Teknologi Militer Dunia• Globalisasi dan Konflik Antar Negara• Transnational Organized Crimes• Rangkuman
53
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 53 7/10/12 2:11 PM

Bab III.
Globalisasi dan Revolutionary in Military Affairs
Sebagai sebuah fenomena sosial, globalisasi yang ada saat ini memberikan pengaruh yang luar biasa bagi masyarakat, tak terkecuali bagi institusi militer yang merupakan bagian dari masyarakat suatu negara. Dalam perkembangannya kemudian, pada ranah militer, muncul terminologi Revolutionary in Military Affairs (RMA), atau yang jika di-Indonesia-kan kurang lebih revolusi dalam urusan-urusan kemiliteran, bisa juga hal ini dimaknai sebagai transformasi dalam dunia militer. Munculnya RMA ini tidak terlepas dari sejarah perkembangan masyarakat dunia itu sendiri. Secara sosiologis setidaknya, RMA bisa dihubungkan dengan bagaimana masyarakat dunia memaknai dan mengelola pertentangan dan konflik yang melibatkan kekuatan militer negara-negara. Oleh karenanya, pertanyaan pokok yang hendak diajukan dalam bagian ini adalah, seberapa besar keterkaitan antara persoalan globalisasi dengan wacana dan praktik revolusi dalam urusan-urusan kemiliteran itu sendiri.
3.1. Globalisasi dan Keamanan Nasional
Berdasarkan beberapa cara pandang mengenai globalisasi dan keamanan nasional pada bab sebelumnya kita bisa mengambil satu benang merah yang cukup kuat, bahwa globalisasi, terutama pasca Perang Dingin telah menimbulkan beberapa gejolak baik di tingkat nasional maupun global. Bahwa globalisasi telah menjadi faktor pendorong, hal itu tentu saja tidak terbantahkan. Namun sejauh mana faktor itu mampu mendorong perubahan-perubahan mendasar dalam kebijakan keamanan nasional suatu negara pada gilirannya menjadi begitu relatif. Bahwa negara-negara di dunia saat ini semakin menyadari perubahan-perubahan yang sangat cepat dalam kaitannya dengan relasi antara berbagai aktor dalam politik internasional, seperti negara, pasar maupun masyarakat sipil. Hal tersebut tidak lantas mendorong kebijakan-kebijakan keamanan nasionalnya sejalan dengan nilai-nilai universal dalam hal transformasi kekuatan militer internasional.
Pada kenyataannya setiap negara, apakah yang tergolong negara kuat ataupun lemah, tidak senantiasa memiliki respon yang sama terhadap apa yang mereka
54
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 54 7/10/12 2:11 PM

definisikan sebagai ancaman itu sendiri. Perbedaan cara pandang inilah yang kemudian menyebabkan kebijakan keamanan nasional satu negara tetap merupakan prerogatif atau otoritas negara itu sendiri. Di sini bisa dikatakan bahwa meskipun terjadi perubahan perimbangan kekuatan dunia, namun otoritas dari suatu negara tidak terkalahkan atau tetap kuat. Meskipun perhitungan dan kalkulasi dalam menyusun kebijakan keamanan nasional tentu setiap saat bersifat dinamis dengan menggunakan indikator serta parameter yang terus berkembang. Di sini, kemampuan suatu negara dalam merumuskan apa-apa yang menjadi ancaman atau tantangan bagi keamanan nasional menjadi begitu penting. Bukan untuk menuruti apa yang menjadi kehendak dari nilai-nilai yang diajukan oleh masyarakat global itu sendiri, melainkan pada bagaimana otoritas suatu negara bisa tetap terjaga dan utuh keberadaannya. Secara umum, hanya bisa dikatakan (mengutip Ripsman dan Paul) dalam konteks globalisasi seperti sekarang ini, negara adalah institusi yang adaptif terhadap tantangan dan ancaman global itu sendiri. Proses adaptif itulah yang pada gilirannya justru memperkuat posisi dan peran negara dalam kancah hubungan internasional.
Penjelasan di atas menyiratkan dua hal mendasar, yakni pertama, bahwa proposisi globalisasi sebagai faktor independen memang betul adanya, dan yang kedua, negara dalam hal ini juga memiliki kemampuan untuk memberikan respon terhadap apa yang menjadi tantangan dan ancaman global. Kemampuan dan otoritas negara untuk memberikan respon terhadap dinamika ekonomi politik global itu sendiri sesungguhnya bisa diartikan sebagai satu bentuk tantangan terhadap proposisi pertama, yang menyatakan bahwa globalisasi adalah sebagai faktor independen yang lebih pada posisi mempengaruhi negara-negara untuk bertindak.
Hal inilah yang perlu digaris-bawahi, karena kemampuan negara dalam merespon secara otonom apa yang disebut sebagai pengaruh global, sesungguhnya menunjukkan bagaimana dinamika global itu sendiri bergerak dan berkembang dari respon-respon yang berbeda-beda tersebut. Dengan kata lain, pada setiap perkembangan globalisasi ataupun pada setiap momentum yang kemudian mendorong terjadinya pergeseran kekuatan politik global ataupun pertentangan-pertentangan baru, negara-negara senantiasa memiliki kemampuan untuk menentukan ke mana arah dan perkembangan relasi internasional itu sendiri. Contoh paling sederhana adalah ketika terjadi penyerangan terhadap menara kembar WTC di New York pada tanggal 11 September 2001, keputusan AS sebagai sebuah negara untuk secara total memerangi terorisme jelas menjadi babak baru dinamika hubungan internasional itu sendiri.
Secara logis fakta sosial ini barangkali juga dimaknai sebagai faktor pemicu dari
55
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 55 7/10/12 2:11 PM

apa yang disebut sebagai revolusi dalam dunia militer karena pada gilirannya telah memicu perang baru di beberapa tempat seperti di Afghanistan, Irak dan Pakistan. Dalam konteks yang paling kontemporer belakangan ini tentu saja, kemampuan Cina untuk mencegah agar AS tidak menjual senjata ke Taiwan menunjukkan satu contoh bahwa Cina sebagai sebuah negara memiliki kemampuan yang cukup kuat untuk bisa memaksakan kepentingan nasionalnya dalam konteks hubungan internasional itu sendiri yang pada gilirannya secara dramatis mengubah konstelasi kekuatan negara-negara di dunia. Pertanyaannya kemudian, secara sosiologis, maka apa yang sesungguhnya bisa kita tarik sebagai sebuah persoalan mendasar dalam konteks hubungan internasional sekarang ini.
Dalam perspektif sosiologik, oleh beberapa kalangan globalisasi dipandang sebagai satu fenomena di mana ia tidak hanya menghadirkan hidangan global di rumah-rumah lokal, melainkan juga menyajikan apa yang ada di wilayah lokal muncul ke panggung global itu sendiri. Dalam banyak hal kiranya, globalisasi dipandang sebagai sebuah paradoks dari perkembangan modernisasi itu sendiri. Oleh karena itu, dalam melihat apa yang terjadi terkait dengan perkembangan globalisasi, khususnya jika dikaitkan dengan persoalan keamanan nasional, globalisasi, mengutip apa yang dikatakan oleh Giddens (2000) dan Ritzer (2003), meskipun globalisasi menurutnya berasal dari Barat dan AS, yang pengaruhnya secara determinan ke dunia Timur, namun harus diakui bahwa globalisasi adalah proses dua arah. Globalisasi menjadi semakin decentred, di mana bangsa-bangsa di luar AS dan Barat juga memiliki kemampuan untuk memainkan peran, bahkan memiliki kecenderungan yang semakin menguat akhir-akhir ini.
Pertanyaan kunci dalam kaitannya dengan sosiologi globalisasi adalah, apakah dunia yang semakin mengglobal ini akan mendorong masyarakat kita semakin homogen dengan nilai-nilai universal yang tersebar sampai pelosok-pelosok kampung, atau globalisasi justru membuka peluang bagi berbagai kalangan untuk eksis secara berbeda satu sama lain sehingga semakin heterogen (Ritzer, 2003). Kendati begitu, menurut penulis, pertanyaan yang justru semakin relevan di masa sekarang ini, bagaimana kita bisa terbebas dari pertanyaan itu sendiri, atau apakah homogenitas dan heterogenitas itu suatu situasi yang memang saling meniadakan atau di antara keduanya justru terdapat kompromi-kompromi serta negosiasi-negosiasi baik di level individu maupun masyarakat yang pada gilirannya justru menempatkan keduanya sebagai sebuah proses yang tidak lantas bertolak belakang, melainkan berjalan seiring dengan pola hubungan yang kontekstual di antara keduanya.
Dengan cara pandang seperti itulah kiranya, persoalan mendasar dari fenomena
56
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 56 7/10/12 2:11 PM

globalisasi yang terkait dengan keamanan nasional suatu negara bisa dimaknai sebagai satu bentuk relasi yang saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga globalisasi dan negara-negara itu tidak satupun yang bisa dilihat sebagai kekuatan yang independen mempengaruhi salah satunya. Keduanya justru berada pada satu derajat yang setara, di mana tidak hanya globalisasi bisa menghadirkan tekanan-tekanan serta ancaman baru bagi satu negara, namun demikian sebaliknya, negara-negara dengan otoritas dan kekuatan yang dimilikinya, secara relatif bisa mempengaruhi bagaimana aturan main global itu disusun dan dijalankan, atau bagaimana nilai global yang pada gilirannya menjadi faktor pemaksa suatu negara itu justru berasal dari semangat suatu negara dalam merespon persoalan-persoalan di dalam negaranya maupun ancaman dari luar. Dengan kata lain, persoalan mendasar dari globalisasi dan keamanan nasional itu adalah, seberapa besar derajat kekuatan suatu negara dalam melihat dan memaknai globalisasi itu sendiri sehingga negara tersebut mampu merumuskan strategi dalam mengatasi persoalan-persoalan keamanan nasionalnya sekaligus menjaga harmoni hubungan internasionalnya dengan negara-negara lain.
3.2.
Perkembangan Pemikiran Revolutionary in Military Affairs
Konsep RMA pertama kali digunakan secara akademik pada tahun 1955. Kajian mengenai revolusi militer ini muncul karena temuan dari beberapa ilmuwan mengenai adanya kecenderungan pada bagian tertentu dalam sejarah pada abad ke-16 dan 17 bahwa suatu inovasi atau kombinasi dalam beberapa bidang mempunyai implikasi terhadap transformasi dalam penyelenggaraan perang. Sementara itu, pada waktu Perang Dingin, militer Uni Sovyet sangat memperhatikan terhadap kajian revolusi militer khususnya pada dampak penggunaan teknologi senjata nuklir. Pada perkembangan selanjutnya, konsep RMA ini juga dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan Barat sehingga konsep ini dikenal luas dalam lingkungan militer AS pada tahun 1980.
Dalam mengkaji konsep RMA terdapat tiga kubu pemikiran, yang jika kita telusuri akar dari perbedaan pemikiran ini bersumber pada faktor penyebab munculnya RMA. Aliran pemikiran pertama, diwakili oleh Andrew Kepinevich, James Adam, Collin Gray, dan Williamson Murray. Sedangkan aliran pemikiran kedua, diwakili oleh Alvin Toffler dan Heidi Toffler. Terakhir, aliran pemikiran ketiga, para ahli yang mencoba mensintesakan kedua aliran pemikiran sebelumnya.
57
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 57 7/10/12 2:11 PM

Para ahli pemikiran pertama memfokuskan pada pengaruh teknologi terhadap RMA dan mereka juga menggangap bahwa revolusi militer juga dapat mempengaruhi dan merubah sifat dasar masyarakat dan negara. Andrew Kepinevich (dalam Tim Benbow, 2004) mengidentifikasi sebanyak sepuluh pokok-pokok revolusi dalam urusan kemiliteran, yaitu: (1) revolusi infantri, (2) revolusi artileri, (3) revolution of sail and shot at sea pada abad ke-16 dan abad ke-17, (4) revolusi benteng pada abad ke-16, (5) revolusi bubuk mesiu, (6) revolusi Napoleon, (7) revolusi perang darat pada abad ke-19, (8) the naval revolution pada abad ke-19, (9) the interwar revolution dalam mekanisasi, penerbangan, dan informasi, dan (10) revolusi nuklir. Walaupun teknologi dianggap sebagai hal yang fundamental yang menyebabkan terjadinya RMA, tetapi teknologi bukanlah satu-satunya faktor yang dominan. Karena, realitas yang ada merefleksikan bahwa perubahan teknologi dalam militer tidak serta merta diikuti juga perubahan dalam aspek doktrin dan organisasi. Krepinevich (dalam Tim Benbow, 2004) mengemukakan bahwa revolusi militer sebagai suatu hal yang terjadi ketika penerapan teknologi baru ke sejumlah sistem militer yang signifikan dikombinasikan dengan inovasi konsep dan adaptasi operasional dalam suatu cara tertentu yang secara mendasar merubah karakter dan penyelenggaraan perang. Dalam definisi RMA yang dikemukakan oleh Krepinevich ini terkandung secara eksplisit bahwa teknologi bukanlah faktor dominan dan memiliki kaitan yang erat pada perkembangan dan adaptasi pada aspek lain. Kita dapat merujuk pada contoh RMA yang timbul karena didorong oleh adanya faktor sosial dan politik seperti Revolusi Perancis dan perang-perang Napoleon (Napoleonic Wars). Hal ini lebih dominan faktor sosial dan politik dibandingkan faktor teknologi.
Berbagai realitas ini memacu munculnya pemikiran aliran lain yang menekankan bahwa RMA merupakan bagian dari transformasi dalam aspek politik, ekonomi dan sosial. Pemikir utama aliran ini seperti Alvin Toffler dan Heidi Toffler. Menurut mereka penggunaan senjata api, kapal selam, dan pesawat tempur memang membawa perubahan dalam perang, tetapi hal ini hanya menambah elemen baru terhadap hal yang sesungguhnya telah ada. Perubahan senjata bukanlah sebuah RMA menurut mereka; tetapi merupakan sub dari RMA. Bagi mereka RMA merupakan suatu perubahan secara revolusioner yang mengubah “permainan” itu sendiri termasuk peraturan, peralatan, ukuran, organisasi dalam tim, pelatihan, doktrin dan taktik. Mereka juga memahami konsep revolusi sebagai suatu peradaban baru yang menantang peradaban sebelumnya dan berimplikasi pada transformasi segala aspek dalam dunia militer.
Alvin Toffler dan Heidi Toffler membagi RMA pada tiga gelombang. Gelombang pertama, pada masa pra modern, di mana sistem kehidupan masyarakat berbasiskan
58
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 58 7/10/12 2:11 PM

agraria atau pertanian dan perang pun merefleksikan kehidupan mereka dan lebih disebabkan oleh masalah pertanian. Tentara dibayar oleh tuan tanah dan perkembangan senjata pun masih sangat sederhana. Kekuatan utama adalah tenaga tentara itu sendiri. Gelombang kedua terjadi pada masa revolusi industri. Pada masa ini senjata diproduksi secara massal (dalam jumlah yang banyak). Dan perang pun menggunakan pasukan dalam jumlah yang besar serta kerusakan akibat perang juga sangat luas. Di samping itu, tentara tidak lagi dibayar oleh tuan tanah tetapi merupakan perwujudan loyalitas mereka kepada negara bangsa. Hal ini dikembangkan oleh Napoleon dengan memaksa wajib militer di kalangan pemuda Perancis. Transformasi ini juga mempengaruhi transformasi dalam organisasi militer untuk menciptakan organisasi yang profesional. Revolusi Industri juga berpengaruh pada perkembangan teknologi persenjataan. Salah satunya dengan penemuan bubuk mesiu sebagai bahan dasar untuk senjata api dan penemuan mesin-mesin sehingga dapat memproduksi secara massal senjata. Yang selama ini produksi senjata sepenuhnya menggunakan tenaga manusia. Terakhir, gelombang ketiga, yang mulai muncul sejak pecahnya Perang Teluk pada tahun 1991. Pada masa ini kecenderungan perang menuju pada peperangan informasi dengan menggunakan teknologi canggih yang memiliki keakuratan yang tajam, sifat kerusakan yang dapat disesuaikan. Pada gelombang ini juga terjadi perubahan paradigma dalam dunia militer. Mereka membutuhkan tentara yang cerdas, memiliki keahlian yang baik, dan senjata yang canggih sehingga pada akhirnya, organisasi militer lebih dibentuk pada organisasi yang jumlah anggotanya relatif kecil dan bersifat fleksibel.
Aliran pemikiran RMA yang ketiga, yakni para ilmuan yang mensintesakan kedua pemikiran sebelumnya. Asumsi yang mereka bangun adalah teknologi pada kenyataannya bukan merupakan aspek yang cukup untuk terjadinya RMA. Eksistensi teknologi bukanlah faktor dominan terciptanya RMA, kecuali jika diikuti oleh perubahan dalam aspek doktrin militer dan organisasinya. Berangkat dari pandangan ini para ahli aliran pemikiran ini membagi RMA dalam tiga aspek, yaitu perubahan secara revolusioner pada teknologi, doktrin dan organisasi (Elinor C. Sloan, 2002). Revolusi teknologi menyebabkan adanya perubahan dalam strategi, organisasi dan peralatan militer dari masa sebelumnya. Dengan adanya revolusi tersebut, maka teknologi semakin mempertajam keakuratan dalam perang atau dengan kata lain dapat mengeliminir “fog of war”. Revolusi teknologi ini terdiri dari precision force and precision guided munitions, force projection and stealth dan battle space awareness and control. Dewasa ini teknologi diciptakan dengan mengutamakan kecanggihannya, bukan pada ukuran besarnya atau dampak kerusakan yang luas. Teknologi senjata yang dibutuhkan
59
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 59 7/10/12 2:11 PM

adalah yang memiliki keakuratan dalam menentukan sasaran sehingga dalam perang, terbunuhnya masyarakat sipil dapat diminimalisir. Senjata rudal merupakan salah satu bentuk precision force. Tomahawk cruise missile merupakan senjata Angkatan Laut AS dan Inggris yang dipandu dengan global positioning system (GPS). Senjata ini dapat menghancurkan sasaran dalam ukuran kecil yang terletak jauh ribuan Nautical Mile (NM). Contoh senjata yang menggunakan teknologi precision force and precision guided munitions yaitu bom yang canggih atau yang dikenal dengan “smart bomb”. Bom itu memiliki kecepatan, jarak dan keakuratan yang dapat menghancurkan sasaran dalam waktu yang singkat dan mematikan.
Revolusi teknologi yang kedua yakni force projection and stealth. Dengan adanya revolusi teknologi ini munculnya senjata-senjata atau kendaraan-kendaraan yang tidak dapat terdeteksi oleh radar sehingga dapat mengelabui musuh. Senjata atau kendaraan tersebut memiliki fitur stealthy contohnya helikopter Comanche armed reconnaissance. Revolusi teknologi yang terakhir yakni battle space awareness and control. Salah satu bentuk teknologi ini adalah satelit. Satelit dapat memantau wilayah pertempuran dan posisi lawan dari jarak yang jauh sehingga kehadiran pasukan atau komandan secara fisik di wilayah pertempuran dapat diminimalisir. Teknologi battle space awareness and control juga mempengaruhi organisasi dalam militer. Organisasi militer harus beradaptasi terhadap teknologi yang ada. Dengan adanya kemajuan teknologi ini konsep strategi memenangkan perperangan pun mengalami pergeseran. Konsep Komando dan Kendali (Kodal atau K2) yang selama ini dominan diaplikasikan menjadi kurang mumpuni. Pemenangan perang tidak hanya tergantung pada hubungan intern antara komandan dan anak buahnya dalam tugas operasi tetapi meliputi berbagai aspek lainnya sehingga konsep yang berkembang dewasa ini yakni K4IMP (Komando, Kendali, Komunikasi, Komputer, Intelijen, dan Manajemen Pertempuran) sebagai satu kesatuan yang utuh dalam rangka memenangkan pertempuran. Kecenderungan perkembangan teknologi ini akan menuju pada peperangan informasi.
Selanjutnya, aspek yang kedua dalam RMA, yakni revolusi doktrin. Revolusi teknologi dan revolusi doktrin dalam militer bukanlah dua hal yang terjadi secara terpisah akan tetapi revolusi doktrin merupakan pengaruh dari revolusi teknologi. Doktrin militer yang muncul kemudian adalah doktrin bersama. Perkembangan dewasa ini, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Angkatan Darat melakukan kerjasama dalam suatu pertempuran. Ketiga kekuatan ini berintegrasi untuk mencapai tujuan bersama (menghancurkan kekuatan musuh). RMA juga mempengaruhi perubahan doktrin dalam Angkatan Laut. Transisi doktrin Angkatan Laut ini bergeser pada “daratan”
60
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 60 7/10/12 2:11 PM

atau lebih tepatnya peperangan pada daerah pesisir (littoral warfare). Konsekuensinya adalah Angkatan Laut tidak hanya mempersiapkan pada perang di lautan tetapi lebih perhatian pada membangun kekuatan laut untuk menuju perang di daratan. Pada akhirnya, Angkatan Laut akan mengubah Tomahawk land attack cruise missile yang pada mulanya hanya sebagai sebuah senjata strategi menjadi tujuan serangan ke darat (from strategic weapon to strike target ashore).
Perubahan doktrin tidak hanya terjadi pada Angkatan Laut, tetapi juga pada doktrin Angkatan Darat. Operasi-operasi militer lebih mengedepankan pasukan dalam kelompok-kelompok yang relatif kecil pada saat pertempuran. Artinya kekuatan perang lebih bersifat non linear dan terpencar bukan berbentuk kesatuan. Strategi perang akan lebih memprioritaskan pada mobilitas yang bersifat menyerang. Sementara itu, perubahan doktrin juga terjadi pada doktrin Angkatan Udara. Yang pada mulanya menganut manned fighters menjadi unmanned combat. Konsekuensi penerapan doktrin unmanned combat jika terjadi pertempuran, maka pilot mengendalikan pesawat dengan teknologi canggih yang menggunakan satelit secara langsung di luar area pertempuran. Implementasi doktrin ini membutuhkan biaya yang tinggi, tetapi sebaliknya juga dapat meminimalisir risiko tewasnya para pilot tempur. Di sisi yang lain, angkasa luar akan menjadi area utama dalam peperangan di masa yang akan datang. Karena perang yang akan terjadi adalah peperangan informasi (satelit-satelit). Satelit yang digunakan suatu negara akan mendapatkan ancaman atau menjadi ancaman bagi negara lainnya sehingga hal ini memacu pada pemusatan kekuatan militer akan berada pada satelit pada era perang informasi ini.
RMA juga terjadi dengan adanya revolusi dalam organisasi militer. Organisasi militer lebih ditransformasikan pada jumlah yang relatif kecil, akan tetapi memiliki keahlian yang baik dan pendidikan yang tinggi. Pada tataran teoritis, revolusi teknologi, revolusi doktrin dan revolusi organisasi militer berjalan secara simultan. Dengan adanya teknologi yang canggih maka membutuhkan tentara yang mumpuni atau adaptasi organisasi dan tentunya juga adaptasi doktrin. Pada akhirnya, akan timbul organisasi militer dalam format yang baru yang profesional dengan menyeimbangkan antara kualitas dan kuantitas. Hal ini juga berdampak pada perubahan sistem birokrasi dalam militer yang pada mulanya menganut sistem sentralisasi menuju sistem desentralisasi. Sistem yang pertama hanya petinggi militer yang mengetahui informasi pada pertempuran sedangkan sistem yang kedua prajurit biasa juga dapat mengetahui informasi tersebut. Konsekuensinya adalah perubahan dalam “jalur komando”. Jika sebelumnya tentara harus meminta ijin terlebih dahulu kepada komandan yang
61
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 61 7/10/12 2:11 PM

3.3. Belanja Teknologi Militer Dunia
Perkembangan teknologi militer di dunia pada dasarnya tidak terlepas dari dua hal, yang pertama, adanya ancaman terhadap keamanan nasional suatu negara dan yang kedua adanya kebutuhan dari industri senjata di negara maju untuk menjual produksinya di negara-negara berkembang. Dalam kaitan dengan RMA, perkembangan teknologi militer bisa dilihat dari dua sisi yang berbeda, yang melihat RMA kemudian mendorong transformasi militer suatu negara yang salah satunya adalah modernisasi Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista), sedangkan dari sisi yang berlawanan justru melihat bahwa perkembangan teknologi persenjataan di negara-negara majulah yang mendorong kebutuhan bagi negara-negara berkembang untuk melakukan RMA itu sendiri.17
Sebuah analisis yang dipublikasikan Global Fire Power (GFP) belum lama ini memberikan bukti yang obyektif untuk menunjukkan peta kekuatan militer negara-negara di seluruh dunia. Berdasarkan uji data yang mendukung kekuatan militer, daya tahan, stamina dan survival yang mendukungnya, Indonesia sebenarnya berada pada urutan ke-18, menduduki puncak klasemen di kawasan ASEAN. Hasil survey
17 Negara-negara maju yang menjadi produsen senjata itu tidak lain adalah lima negara anggota Dewan Keamanan PBB, yakni Cina, AS, Rusia, Perancis, dan Inggris (Sumber dari Richard F. Grimmet, CRS Report for Congress).
berwenang jika ingin melakukan tembakan, saat ini perwira tersebut hanya melakukan kontak kepada operator yang mengendalikan sistem persenjataan. Perubahan organisasi juga berdampak pada sistem karir. Karir yang tersedia tidak hanya untuk bertempur dalam perang tetapi terdapat berbagai pilihan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan dalam organisasi militer tersebut. Tabel di bawah ini menggambarkan pemetaan perkembangan konsep mengenai RMA.
62
Tabel 3. Perkembangan Konsep RMA
Sumber: Diolah dari berbagai sumber
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 62 7/10/12 2:11 PM

GFP yang memberikan data Peringkat Kekuatan Militer Indonesia ini didapatkan dari berbagai sumber dengan menganalisis 45 faktor, yang intinya melakukan penilaian berdasarkan gelar statis dari jumlah kuantitas peralatan yang dimiliki meskipun peralatan ini belum tentu semua siap atau dapat digunakan sewaktu-waktu. GFP juga melakukan pertimbangan penilaian berdasarkan kemampuan militer setiap negara baik di darat, laut, dan udara, dan kemudian menilai dari aspek logistik dan keuangan. Meskipun berada pada urutan relatif di “atas”, bagi beberapa pakar militer di dalam dan di luar negeri, kapasitas militer Indonesia masih perlu ditunjang dengan kompetensi para perwiranya. Analisis GFP seharusnya dimaknai militer Indonesia untuk memacu upaya-upaya kreatifitas secara komprehensif dan holistik pada arena kompetisi agar militer negara-negara lain mengakui bahwa urutan tersebut memang layak diberikan kepada Indonesia.
63
Tabel 4. Peringkat Kekuatan Militer Negara-negara di Dunia tahun 2011
Sumber: http://www.globalfirepower.com/
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 63 7/10/12 2:11 PM

Negara dengan belanja militer terbanyak di AsiaBerdasarkan data Stockholm International Peace Research Institute, disebutkan bahwa banyak negara yang hingga kini belum menyerah untuk mengurangi anggaran pertahanan mereka. Bahkan, belanja militer di negara-negara Afrika dan Amerika Selatan justru meningkat hingga 6 %. Di antara 10 negara di dunia yang mengeluarkan anggaran besar selama 10 tahun terakhir, tercatat 4 negara dari kawasan Asia masuk dalam daftar tersebut. Sementara itu, dari kawasan Eropa tercatat 5 negara memiliki anggaran militer terbesar yaitu Italia, Jerman, Rusia, Perancis, dan Inggris.18 Berikut 4 negara Asia yang menganggarkan miliaran dolar AS selama 2010 untuk kegiatan militer:
CinaBelanja militer 2010: US$119 miliar (perkiraan). Cina merupakan negara kedua di dunia yang menghabiskan dana paling besar untuk belanja militer sepanjang 2010. Negara Tirai Bambu ini juga mengalami pertumbuhan tercepat di antara negara-negara lainnya. Sejak 2001 hingga 2010, tercatat anggaran militer Cina mengalami pertumbuhan yang melesat hingga 189 %. Pertumbuhan itu lebih dari dua kali lipat di antara ke-10 negara yang masuk dalam daftar ini. Pelemahan ekonomi pada 2009 menyebabkan kenaikan anggaran belanja Cina hanya meningkat 3,8 %. Namun, anggaran pada 2011 diperkirakan naik 12,7 %. Banyak analis yang yakin anggaran pertahanan Cina sesungguhnya lebih tinggi dari laporan yang selama ini beredar di masyarakat.
JepangBelanja militer 2010: US$54,5 miliar. Jepang selama ini sudah mempertahankan anggaran militernya hanya sebesar 1 % terhadap PDB sejak 1967. Sebagai hasilnya, penghematan anggaran militer Jepang telah membuat perekonomian negara tersebut semakin kuat. Di saat berbagai negara Asia Timur meningkatkan belanja modal lebih dari 55 % selama 10 tahun terakhir, Jepang justru mengalami penurunan anggaran 1,7 % yang berakibatnya menurunnya belanja modal.
Arab SaudiBelanja militer 2010: US$45,2 miliar. Tingginya anggaran belanja militer Arab Saudi
18 Data mengenai belanja militer ini diunduh dari : http://www.indowebster.web.id/archive/index.php/t-154497.html?s=bb0c8d979e32cd7eab65756fb7557bba
64
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 64 7/10/12 2:11 PM

tidak terlepas dari kekuatan ekonomi yang begitu besar. Anggaran sebesar US$45,2 miliar tahun lalu merupakan 10,4 % dari total Produk Domestik Bruto (PDB) negara Teluk ini. Persentase ini merupakan yang terbesar dibandingkan negara-negara dengan anggaran belanja terbesar dalam daftar 10 negara tersebut. Arab Saudi juga menjadi negara yang mengalami peningkatan belanja militer terbesar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4 %.
IndiaBelanja militer 2010: US$41,3 miliar. India menempati posisi ke-5 di Asia atau ke-9 di dunia sebagai negara yang mengalokasikan dana cukup besar untuk kegiatan militernya. Anggaran belanja militer India tahun lalu sebesar US$1 miliar memang menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, penurunan ini diperkirakan tidak bertahan lama karena pada Februari lalu, pemerintah India kembali meningkatkan belanja militernya sebesar 11,6 %. Hal itu dilakukan seiring makin kuatnya militer di Cina dan Pakistan.
Perkembangan Teknologi Militer Dunia
Pesawat Tempur SilumanSekian banyak Alutsista yang ada, pesawat tempur merupakan salah satu yang menjadi ujung tombak kekuatan Angkatan Udara. Dalam doktrin perang modern, kemampuan pesawat tempur bisa menjadi salah satu penentu jalannya peperangan. Armada pesawat tempur yang tangguh menjadi unsur yang penting dalam suatu operasi militer (pertahanan). Berbeda dari pesawat terbang yang biasa digunakan oleh kalangan sipil, pesawat tempur modern yang digunakan militer saat ini harus memiliki beberapa kriteria wajib, seperti memiliki kemampuan siluman (stealth) yang berguna untuk mengurangi kemungkinan terdeteksinya pesawat oleh radar musuh, avionik yang canggih atau kelincahan bermanuver untuk menghindar dari kejaran pesawat tempur musuh. Bagi dunia penerbangan militer, pesawat tempur siluman memang sedang menjadi pembicaraan hangat.
Pesawat tempur siluman merupakan pesawat tempur yang mampu menyerap dan membelokkan gelombang radar, dengan cara membuat rancang bangun pesawat yang minus lekukan yang fungsinya adalah memperkecil sudut-sudut tajam yang bisa ditangkap oleh radar sehingga memperkecil permukaan yang bisa ditangkap radar,
65
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 65 7/10/12 2:11 PM

Radar Cross Section (RCS), dan membuatnya lebih sulit untuk dideteksi. Hal inilah yang mendasari pesawat siluman memiliki bentuk yang aneh tidak seperti biasanya. Pesawat siluman sebenarnya tidak 100 % tidak bisa terdeteksi radar tetapi karena memiliki RCS yang kecil, sehingga di layar radar hanya tampak seperti gerombolan burung.
Teknologi siluman pertama kali dikembangkan oleh seorang ilmuwan Rusia, Dr. Pyotr Ufimtsev pada tahun 1966. Pada saat ini ada beberapa negara yang sudah mengembangkan pesawat tempur mutakhir berteknologi siluman, mereka berlomba membuat pesawat tempur dengan teknologi yang lebih maju dari yang lainnya. Untuk urusan pesawat tempur siluman, AS menjadi negara yang paling rajin mengembangkannya. Ada beberapa pesawat mutakhir milik AS yang masuk kategori ini, yaitu pesawat F-117 Nighthawk, F-22 Raptor, JSF F-35 Universal Fighter, dan Bomber B-2 Spirit. Kemudian ada Rusia yang juga tak mau kalah dalam membuat pesawat tempur siluman. Rusia sebetulnya sudah mulai membuat program pesawat tempur siluman pada era Uni Sovyet, dengan menyiapkan dua jet tempurnya, yakni Mig 1.44 dan Su-47 Berkut. Tapi dalam perjalanannya program pesawat silumannya terseok-seok. Barulah pada masa kepemimpinan Presiden Vladimir Putin, program ini dilanjutkan kembali. Kemudian lahirlah jet tempur siluman Sukhoi T-50 yang merupakan hasil kerjasama antara Rusia dengan India. Jet tempur ini dirancang mampu menyaingi F-22 Raptor dan JSF F-35 Universal Fighter yang terakhir dan yang paling menggegerkan dunia kedirgantaran adalah munculnya Cina yang berhasil membuat pesawat tempur siluman J-20 Black Eagle sekaligus membuktikan sebagai negara superpower baru, khususnya di bidang teknologi dirgantara. Namun diyakini pesawat tempur tersebut menggunakan teknologi yang dimiliki AS. Cina diduga “mencuri” teknologi stealth dari pesawat tempur siluman F-117 Nighthawk milik AS yang ditembak jatuh pada tanggal 27 Maret 1999 dalam Perang Kosovo.19
Senjata Canggih Buatan Amerika Serikat.20
1. Senapan Personnel Halting and Simulation Response (PHASR). Senapan ini tak akan melukai siapapun, karena senapan ini adalah sistem laser yang
19 Diunduh dari : http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/10/24/163892/18/KF-XIF-X-Jet-Siluman-Buatan-Indonesia-Korsel20 Data mengenai senjata-senjata canggih buatan Amerika Serikat ini diunduh dari : http://indo-defense.blogspot.com/2011/09/new-york-idb-sebagai-negara-adidaya.html dan http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/246123-5-senjata-canggih-milik-as
66
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 66 7/10/12 2:11 PM

dirancang untuk hanya membuat sasaran tembak mengalami disorientasi dan tak bisa melihat. Senjata sejenis yang menggunakan teknologi ini juga sempat digunakan AS di Perang Irak untuk melumpuhkan musuh yang tak mau berhenti di pos pemeriksaan.
2. Active Denial System. Senjata ini menembakkan gelombang elektromagnet langsung kepada permukaan kulit seseorang, sehingga orang itu akan merasa lemah dan kesakitan. Orang yang terkena akan merasa seperti terbakar sinar matahari. Militer AS menyebutnya sebagai “Goodbye Weapon”.
3. Railgun. Senjata ini memanfaatkan medan magnet untuk melontarkan proyektil dengan kecepatan yang fantastis, hingga tujuh kali kecepatan suara. Senjata ini awalnya hanya ada di cerita fiksi namun kemudian militer AS mengembangkannya dan pada 2008 sempat mengujikannya. Rencananya senjata ini akan benar-benar siap antara 2020-2025.
4. Serangga Hybrida MEMS. Senjata ini lebih canggih daripada sekadar mobil-mobilan yang dikendarai oleh remote control. Dengan mengganti otak serangga dengan chip komputer yang bisa mengendalikan sistem syaraf mereka, maka serangga-serangga atau kupu-kupu dapat dikendalikan terbang ke mana pun diinginkan. Dengan menambahkan mereka dengan kamera video dan mikrofon, serangga-serangga ini menjadi alat mata-mata yang sangat ampuh.
5. Microfon Laser. Ini adalah teknologi yang sudah ada di pasaran. Dengan teknologi ini, seseorang bisa menyadap pembicaraan di sebuah ruangan dari jarak jauh. Caranya: Ketika dua orang berbicara di sebuah ruangan, maka gelombang suara mereka akan tertangkap getarannya di benda padat yang terhubung dengan ruangan, seperti jendela ruangan. Dengan senjata laser yang tak terlihat mata bisa diarahkan ke jendela, sehingga akan menerima pantulan laser dari jendela tersebut. Dari pengolahan terhadap gelombang laser hasil pantulan dari jendela, senjata akan menerjemahkannya kembali menjadi sebuah bentuk percakapan suara yang ada di ruangan tadi.
Senjata Anti Tank produksi PT. Pindad yang mematikanIndonesia melalui PT. Pindad, mempunyai tiga produk Senapan Penembak Runduk (SPR) atau senapan sniper anti material tank yang berkualitas dunia. Senapan ini bisa menembus baja yang tebalnya tiga sentimeter dari jarak 900 meter. SPR produksi PT Pindad ada tiga varian, SPR-1, SPR-2 dan SPR-3. SPR-1 dirancang menggunakan munisi kaliber 7,62 mm dengan jarak efektif 900 meter, kemudian SPR-2 dengan sistem
67
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 67 7/10/12 2:11 PM

bolt action dan menggunakan munisi berkaliber 12,7 mm, di mana pada jarak efektif 500 meter mampu menembus berbagai jenis material, dan bahkan mampu merobek baja dengan ketebalan dua sentimeter. SPR-3 dengan kemampuan yang relatif sama dengan pendahulunya namun lebih kuat dan dapat merobek baja dengan ketebalan tiga sentimeter. 21
Selain itu juga terdapat beberapa rencana dan keinginan dari beberapa negara dalam kemajuan teknologi, terkait dengan kecanggihan dan kemajuan di bidang teknologi, dan semuanya tidak terlepas dari upaya untuk menjaga keamanan nasional negaranya. Beberapa teknologi canggih tersebut adalah:22
• Cina membangun jaringan pangkalan rudal nuklir di bawah tanah sepanjang 5.000 kilometer di perbatasan utara negeri tersebut. Pangkalan-pangkalan rudal tersebut sama sekali tidak dapat dideteksi musuh. Militer Cina diperkirakan mempunyai 150-400 rudal dengan hulu ledak nuklir. Namun, sejumlah pakar memperkirakan, bisa saja Cina memiliki rudal nuklir dua kali lipat dari perkiraan selama ini.
• Iran akan menguji bio-kapsul, yang mampu mempertahankan kehidupan makhluk hidup di ruang angkasa. Peluncuran itu akan melibatkan roket pembawa satelit, Kavoshgar 5 (Explorer). Uji coba bio-kapsul tersebut akan memberikan Badan Antariksa Iran pengetahuan penting dalam mengembangkan sistem pendukung kehidupan di ruang angkasa.
• Swedia akan mengembangkan Jubah ajaib yang bisa membuat orang “menghilang”. Para ahli teknologi militer kini telah merekayasa jubah kamuflase tembus pandang yang melindungi tank dari radar pendeteksi panas milik musuh. Tak hanya itu, teknologi baru ini bisa memindai gedung-gedung atau tanah lapang, lalu mereproduksi pola panas dan dinginnya pada panel yang terletak di lambung kendaraan militer. Perangkat kamuflase ini sedang dikembangkan oleh ilmuwan BAE System di Swedia.
• Perangkat mata-mata terbaru militer AS yang lebih mirip mainan anak-anak. Namun perangkat baru ini merupakan perangkat tercanggih dunia. Angkatan Udara AS mengembangkan miniatur pesawat mata-mata super kecil berwujud burung, bahkan berbentuk serangga, yang keberadaannya bisa luput dari
21Jenis senjata buatan PT. Pindad ini diunduh dari : http://indo-defense.blogspot.com/2011/08/senjata-anti-tank-produksi-pindad-yang.html22 Beberapa data mengenai perkembangan senjata mutakhir diunduh melalui : http://indo-defense.blogspot.com
68
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 68 7/10/12 2:11 PM

perhatian. Micro Air Vehicles (MAVs) dikembangkan di Wright-Patterson Air Force Base di Dayton, Ohio. Misi Laboratorium Riset Angkatan Udara ini yakni mengembangkan MAVs yang mampu mencari, melacak dan mengunci posisi musuh sembari beroperasi di lingkungan kota yang rumit.
3.4. Globalisasi dan Konflik Antar Negara
Globalisasi yang dalam prosesnya melahirkan pergeseran konstelasi kekuatan ekonomi politik internasional selama beberapa kurun waktu tidak saja berakibat pada semakin menajamnya konflik antar negara, namun juga sebaliknya pada beberapa kasus mendorong munculnya resolusi konflik di dalam internal negara. Di sini kita bisa melihat, bahwa faktor pendorong paling dominan dari naiknya eskalasi konflik antar negara seringkali adalah dikarenakan persoalan dominasi yang secara bergiliran dilakukan oleh negara-negara yang secara tradisional menjadi kelompok pemenang perang. Sementara resolusi-resolusi konflik yang muncul mencerminkan peran penting kelompok negara-negara mediator yang seringkali diwakili oleh tokoh-tokoh dari kelompok negara-negara maju.
Berakhirnya Perang Dingin mendorong munculnya AS sebagai satu-satunya negara adikuasa yang kemudian banyak memberikan pengaruh bagi persoalan-persoalan keamanan nasional. Penjelasan Robert G. Patnam menyatakan bahwa telah terjadi pendalaman dari globalisasi pasca Perang Dingin, satu proses yang terkait dengan apa yang disebut dengan pertumbuhan keterkaitan-keterkaitan internasional yang di dalamnya juga terjadi secara bersamaan erosi dari otonomisasi dari kedaulatan negara yang pada gilirannya memunculkan satu lingkungan keamanan yang sebelumnya tidak terpikirkan. Proses ini juga selanjutnya memberikan dorongan bagi pergeseran pola konflik dari yang semula sekadar perlindungan terhadap negara menjadi begitu luas cakupannya 23. Sebagai contoh, Azizian (2005) menegaskan bahwa runtuhnya sistem komunisme Uni Sovyet dan lahirnya negara-negara baru di bekas kawasan Uni Sovyet adalah salah satu faktor semakin meluasnya pengaruh global, menstimulasi integrasi ekonomi dan pengembangan civil society. Hal ini mengakibatkan konflik yang beragam di bekas negara-negara Uni Sovyet, termasuk bentuk-bentuk pemberontakan atas dasar ideologi maupun identitas 24. Senada dengan Azizian, Leane Piggot dalam kajiannya yang membahas globalisasi setelah 11 September 2011, juga mengetengahkan keruntuhan Uni Sovyet membuat globalisasi telah menjadikan proses ekonomi diasosiasikan
69
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 69 7/10/12 2:11 PM

sebagai merajalelanya model pembangunan kapitalis di dunia. Kenyataan tersebut
pada gilirannya memunculkan sentimen anti AS yang ditunjukkan dengan gelombang
perlawanan besar terorisme yang melampaui batas-batas teritorial satu negara 25.
Dari penjelasan di atas, kiranya kita bisa membedakan dengan jelas, bahwa
pergeseran konflik di level dunia (internasional) pada dasarnya menjadi faktor
pendorong yang cukup kuat dari terjadinya konflik, kekerasan dan perlawanan di
level yang lebih kecil, seperti negara. Jika merujuk pada sejarah peradaban bangsa-
bangsa di dunia, kiranya kita bisa klasifikasikan konflik-konflik yang terjadi menjadi
beberapa kurun waktu, yang pertama adalah pra Perang Dunia, Perang Dunia Pertama,
Perang Dunia Kedua, Perang Dingin, pasca Perang Dingin dan pasca 11 September
2001. Menurut hemat penulis, dari ke-6 babakan sejarah perang itu bisa kita lihat
bagaimana sesungguhnya pola konflik itu terjadi. Pertanyaannya mengapa perang,
hal ini tentu saja berangkat dari satu asumsi, bahwa perang adalah ujung dari konflik
23Robert G. Patnam, “Globalization, The End of Cold War, and The Doctrine of National Security”, dalam (ed), Globalization and Conflict: National Security in a ‘New’ Strategic Era. (NY, Routledge. 2005)24 Rouben Azizian, 2005, “Russian America and New Conflicts in Central Asia”, dalam Patnam (ed), Globalization and Conflicts: National Security in a ‘New’ Strategic Era. (NY, Routledge,2005)25 Leanne Pigion, 2005, “Globalization, Power and Reform In The Middle East”, dalam Patnam (ed), Globalization and Conflicts: National Security in a ‘New’ Strategic Era. (NY, Routledge,2005)
70
Tabel 5. Pola Konflik dan Polarisasi Kekuatan Dunia
Diolah dari berbagai sumber
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 70 7/11/12 11:29 AM

itu sendiri. Perang tidak mungkin terjadi tanpa disertai oleh konflik terlebih dahulu. Penyebab konflik mungkin beragam, tapi perang tanpa konflik adalah sesuatu hal yang mustahil. Oleh karena itu, dalam setiap periode perang itu, dapat dilihat sejauh mana pola dan pengaruhnya terhadap perkembangan masyarakat dunia. Tabel di atas yang diramu dari berbagai sumber oleh penulis, kiranya bisa menjelaskan secara singkat, bagaimana relasi antara perang, pola konflik serta konsekuensi-konsekuensi yang muncul, terutama konsekuensi ekonomi politik serta hubungan internasionalnya.
Dari beberapa sumber yang menjelaskan perihal konflik di dunia, sekilas tidak nampak adanya satu keterkaitan antara satu periode dengan periode yang lain, namun jika kita telisik lebih dalam, justru setiap periode perang tersebut terdapat beberapa hal yang menjadi semacam jembatan penghubung bahwa konflik yang terjadi seolah menemukan kontinuitasnya. Kondisi seperti itu bisa kita lihat jika mencoba membandingkan pihak-pihak pemenang perang pada setiap periode adalah pihak yang kemudian akan bertikai pada periode berikutnya. Oleh karena itu konflik dunia yang kemudian mendorong terjadinya perang besar di dunia tidak bisa dinafikan merupakan kelanjutan dari konflik-konflik yang telah ada sebelumnya. Sebagian besar dari konflik tersebut pada dasarnya masih berkutat pada persoalan klasik seperti masalah tata batas wilayah dan perebutan sumber daya alam.
Tabel di atas dibuat oleh penulis untuk mengilustrasikan bagaimana konflik yang
71
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 71 7/10/12 2:12 PM

berujung pada perang-perang besar di dunia senantiasa menimbulkan konsekuensi-konsekuensi lanjutan. Dari semenjak awal masa sebelum Perang Dunia, kekuatan di dunia bersifat multipolar, yang artinya tersebar pada beberapa kekuatan pokok seperti kerajaan-kerajaan yang memiliki pasukan yang kuat, armada perang yang besar serta penguasaan teritorial yang luas. Dampak dari konflik dan perang pada masa sebelum Perang Dunia Pertama adalah pergeseran tata batas kerajaan ataupun munculnya koloni-koloni di berbagai benua. Sementara itu, masa Perang Dunia Pertama yang memunculkan kubu Sekutu (Inggris Raya, AS, Rusia, Jepang, Itali, Perancis, dan Belgia) yang melawan kubu Poros (Jerman, Austria-Hungaria, Bulgaria, dan Kekaisaran Ottoman) dan dimenangkan oleh Sekutu menjadi basis dari Perang Dunia Kedua dan Perang Dingin itu sendiri. Pada masa Perang Dunia Pertama ini, kekuatan di dunia masih terbagi dan tersebar secara relatif merata di beberapa negara. Kondisi ini seperti halnya pada masa sebelum Perang Dunia masih bisa dikatakan sebagai situasi multipolar, di mana belum ada dominasi satu atau dua negara dalam percaturan politik internasional. Usai Perang Dunia Pertama yang dimenangkan oleh kubu Sekutu, konsekuensi paling kongkret adalah terjadinya revolusi di beberapa negara serta tumbangnya kekuasaan monarki absolut di beberapa negara yang sebelumnya menggunakan sistem kerajaan.
Masa Perang Dunia Kedua adalah kelanjutan dari Perang Dunia Pertama, hal ini paling tidak bisa dijelaskan dari pihak-pihak yang bertikai pada masa ini. Masih melibatkan antara kubu Poros (Jerman, Jepang, Rumania, Hungaria, Itali) dan kubu Sekutu (AS, Rusia, Inggris, Perancis, Cina, Yugoslavia). Pada masa ini kekuatan dunia masih relatif tersebar sehingga bisa dikatakan bersifat multipolar. Perang Dunia Kedua sekali lagi dimenangkan oleh kubu Sekutu yang konsekuensinya adalah munculnya negara bangsa baru di beberapa wilayah di Afrika dan Asia yang menandai era baru dari sistem politik dunia dan awal dari gejolak Perang Dingin.
Masa selanjutnya adalah era Perang Dingin yang melibatkan dua negara besar di dunia, yakni Uni Sovyet dan AS. Keduanya adalah sama-sama pemenang Perang Dunia kedua yang pada gilirannya menjadi kekuatan super power dunia. Keduanya mewakili ideologi politik yang saling berlawanan, yang pertama mewakili sistem sosialisme komunis dan yang kedua mewakili liberal kapitalisme. Konflik pada masa Perang Dingin tidak secara massif melahirkan perang besar, namun secara ekonomi politik memiliki imbas yang sangat kuat pada negara-negara di dunia. Pada masa ini, dunia terbelah menjadi blok Barat dan blok Timur (bipolar). Perang Dingin dimenangkan oleh AS ditandai dengan runtuhnya Uni Sovyet. Konsekuensinya adalah munculnya negara-negara baru pecahan Uni Sovyet serta bubarnya Republik Federal Yugoslavia.
72
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 72 7/10/12 2:12 PM

Berakhirnya era Perang Dingin juga ditandai dengan bersatunya kembali Jerman Barat dan Jerman Timur, menjadi Republik Federal Jerman.
Pada era pasca Perang Dingin otomatis AS menjadi satu-satunya negara adidaya di dunia. Percaturan politik dunia tidak bisa tidak berada di tangan AS yang juga berperan sebagai “polisi dunia”. Nilai-nilai universal yang disosialisasikan secara massif seringkali adalah nilai-nilai yang bersumber dari apa yang telah dilakukan oleh AS, seperti demokratisasi dan HAM. Kekuasaan unipolar di tangan AS memudahkan mereka untuk memaksakan segala macam agenda ekonomi politik mereka pada negara-negara di dunia. Indonesia menjadi salah satu contoh betapa persoalan pelik pasca Perang Dingin menjadi latar dari lepasnya Timor Timur melalui sebuah operasi militer pihak luar yang dibungkus dengan bahasa intervensi kemanusiaan atas konflik di pulau Timor bagian timur tersebut 26.
Namun demikian, konflik tidak juga usai dengan adanya penguasa tunggal dunia. Ditandai dengan penyerangan WTC di New York dan markas angkatan bersenjata AS, Pentagon, muncullah gelombang terorisme yang mengatas namakan Islam yang menentang hegemoni AS dan Barat. Pasca serangan 11 September 2001 ini, AS bersama sekutunya melancarkan invasi ke Irak dan Afganistan yang mereka klaim sebagai tempat teroris bersembunyi. Bukannya meredam perlawanan kelompok teroris, hal ini justru memicu gelombang bom bunuh diri di beberapa tempat di dunia. Slogan menciptakan negara yang demokratis di Irak dan Afghanistan dianggap oleh sebagian kalangan sebagai upaya Barat memaksakan agenda-agenda politik mereka di negara-negara Islam. Selain itu, tak kunjung usainya konflik Israel dan Palestina menjadi semacam ganjalan bagi upaya AS dan Barat membangun jembatan komunikasi dengan negara-negara Arab dan Islam khususnya.
Persoalan terorisme pada gilirannya merembet pada persoalan ekonomi politik yang cukup nyata termasuk di dalamnya pergeseran konstelasi kekuatan ekonomi dunia saat ini. Dalam konteks kekinian, AS yang sebelumnya menjadi satu-satunya negara super power di dunia mengalami persoalan yang cukup rumit dengan krisis ekonomi. Demikian juga dengan negara-negara barat yang tergabung di dalam Zona Uni Eropa, beberapa dari mereka ikut terkena imbas krisis ekonomi yang sangat parah. Sementara itu, meskipun masih dilihat sebagai kelompok negara berkembang, Cina muncul sebagai satu-satunya kekuatan ekonomi dunia yang masih terus menunjukkan
26 Anthony Howard, 2005, “Humanitarian Intervention in East Timor : Some ingredients for sustainable security?”, dalam Patnam (ed), Globalization and Conflicts: National Security in a ‘New’ Strategic Era. (NY, Routledge,2005)
73
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 73 7/10/12 2:12 PM

kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang positif. Bahkan dalam beberapa hal ekonomi Cina menjadi penopang dari ekonomi AS dan sebagian besar negara-negara Eropa. Saat ini, Cina telah muncul sebagai salah satu raksasa ekonomi dunia yang cukup kuat. Investasi ekonomi negara tirai bambu ini yang tersebar di negara-negara Eropa, Afrika, AS dan Asia menjadikan Cina sebagai satu-satunya negara yang bisa membantu AS menanggulangi krisis ekonominya. Kejatuhan ekonomi AS dan Eropa secara kualitatif telah menurunkan derajat kekuasaan tunggal AS. Jika ditilik lebih dalam, kekuasaan saat ini cenderung terbagi di antara negara-negara AS, Cina, Rusia dan beberapa negara Eropa, cenderung multipolar seperti sebelum masa Perang Dingin dan ada kemungkinan mengarah pada pemusatan kekuatan antara AS dan Cina (bipolar). Tanda-tandanya ditunjukkan pada dampak level mikro dari persaingan antara AS dengan Cina paling tidak bisa kita saksikan dengan munculnya negara baru di Afrika, yakni Sudan Selatan, serta gelombang revolusi di negara-negara Timur Tengah.
Pertanyaannya kemudian, mungkinkah situasi bipolaritas itu akan muncul di masa yang akan datang, mengingat saat ini secara de facto hanya AS dan Cina saja yang secara ekonomi maupun politik memiliki kesempatan untuk mendominasi dunia. Jika demikian halnya, pertanyaan berikutnya yang patut diajukan adalah bagaimana prospek persaingan itu, apakah akan merujuk seperti apa yang terjadi pada masa Perang Dingin, mengingat konflik ini secara idiologis juga mendapatkan tempatnya serta konsekuensi-konsekuensi seperti apa yang akan muncul. Dalam konteks Indonesia, tentu saja bagaimana kita mengelola kepentingan nasional (national interest) dalam dinamika global yang seperti itu menjadi lebih penting untuk ditelaah lebih jauh.
Di samping berbagai persoalan yang telah dikemukakan di atas, kiranya ada satu catatan penting terkait konflik antar negara yang dalam perjalanannya tidak juga menghasilkan resolusi yang optimal. Prinsip win-win solution dalam mengatasi setiap konflik antar negara yang muncul – utamanya konflik perbatasan – pada kenyataannya hanya sebatas slogan atau teori. Contoh-contoh kasus seperti konflik Israel-Palestina, sengketa Kepulauan Spratly dan Paracel di Laut Cina Selatan yang melibatkan beberapa negara, konflik perbatasan Thailand-Kamboja, konflik Ambalat antara Indonesia dan Malaysia belum juga berujung pada proses resolusi. Keadaan ini secara tegas menunjukkan bahwa persoalan wilayah dan tata batas, sepanjang sejarah terus menghiasi pertikaian dan ketegangan di antara negara-negara di dunia. Sulitnya penyelesaian itu dikarenakan adanya kepentingan nasional yang berbeda di antara satu negara dengan negara lain. Perbedaan kepentingan nasional itu pada gilirannya menyandera proses-proses mediasi konflik yang ada, sehingga negosiasi resolusi konflik itu sesungguhnya
74
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 74 7/10/12 2:12 PM

hanya berfungsi sebatas menjaga agar situasi ketegangan tidak berubah menjadi perang tapi tetap belum menyelesaikan konflik yang ada.
3.5.
Transnational Organized Crimes
Seiring dengan pesatnya perkembangan arus informasi dan teknologi, maka muncul pula tatanan kehidupan yang baru dalam berbagai dimensi. Transisi yang terjadi ini akhirnya dapat menghubungkan semua orang dari berbagai belahan dunia, semuanya dapat terkoneksi. Disadari atau tidak, hal ini telah membawa pengaruh yang sangat besar dalam hubungan yang terjalin antar negara. Namun perkembangan globalisasi tak selamanya membawa keuntungan tapi dapat juga menjadi celah dan peluang yang dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan antar negara dengan kemudahan yang ditawarkan oleh arus informasi, teknologi, dan transportasi. Dengan perkembangannya yang demikian pesat, Transnational Organized Crimes (TOC) dewasa ini dipandang sebagai salah satu ancaman serius terhadap keamanan global. Selain berkembang pesat, kejahatan lintas negara seperti itu, memiliki karakteristik yang sangat kompleks. Beberapa faktor yang menunjang kompleksitas perkembangan TOC antara lain: globalisasi, migrasi atau pergerakan manusia, serta perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang pesat. Keadaan ekonomi dan politik global yang tidak stabil juga berperan menambah kompleksitas tersebut.
Pada pertemuan tingkat tinggi yang diselenggarakan di Majelis Umum PBB tanggal 17 Juni 2010, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon menyebutkan bahwa di satu sisi ancaman TOC semakin meningkat namun di sisi lain kemampuan negara untuk mengatasinya masih terbatas. Untuk itu, sangat penting bagi negara-negara untuk meningkatkan kerjasama internasional untuk secara kolektif menanggulangi meningkatnya ancaman TOC tersebut. Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC) yang diadopsi pada tahun 2000 menyebutkan sejumlah kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan ini, yaitu pencucian uang, korupsi, perdagangan manusia, penyelundupan pekerja migran serta produksi dan perdagangan gelap senjata api. Konvensi juga mengakui keterkaitan yang erat antara TOC dengan kejahatan terorisme, meskipun karakteristiknya sangat berbeda. Meskipun kejahatan perdagangan gelap Narkoba tidak dirujuk dalam konvensi, kejahatan ini masuk kategori TOC dan bahkan sudah diatur jauh lebih lengkap dalam tiga konvensi terkait narkoba sebelum
75
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 75 7/10/12 2:12 PM

disepakatinya UNTOC. ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes (ASEAN-PACTC) tahun 2002 juga menyebutkan delapan jenis kejahatan lintas negara dalam lingkup kerjasama ASEAN yaitu perdagangan gelap narkoba, perdagangan manusia, sea piracy, penyelundupan senjata, pencucian uang, terorisme, international economic crime dan cyber crime.
Dalam menanggulangi kejahatan transnasional ini, Indonesia aktif dalam melakukan kerjasama dengan negara-negara lainnya. Sebagai implementasi peran aktif tersebut, Indonesia telah menjadi negara pihak pada lima instrumen internasional yang terkait dengan penanggulangan kejahatan dimaksud yakni:1. UN Single Convention on Narcotics2. UN Convention on Psychotropic Substances3. UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic
Substances4. UN Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC) serta dua Protokolnya
mengenai Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia5. UN Convention Against Corruption (UNCAC).
Seiring perkembangan zaman, terdapat berbagai kejahatan transnasional lainnya yang perlu ditangani secara bersama dalam kerangka multilateral, seperti kejahatan pencurian dan penyelundupan obyek-obyek budaya, perdagangan organ tubuh manusia, environmental crime, cyber crime dan computer-related crime. Dan sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen sebagai negara pihak pada lima instrumen internasional tersebut, pemerintah telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan terkait dengan penanggulangan kejahatan lintas negara yang mengadopsi atau sejalan dengan standar dan norma yang diatur dalam konvensi-konvensi tersebut.
Selain ikut aktif dalam forum sektoral seperti Asia Pacific Group on Money Laundering dan Egmont Group yang membahas isu pencegahan dan pemberantasan isu pencucian uang, pemerintah juga turut berpartisipasi secara aktif dalam berbagai forum internasional terkait dengan penanggulangan kejahatan lintas negara, antara lain:1. Commission on Narcotic Drugs (CND)2. Commission on Crime and Criminal Justice (CCPCJ), termasuk UN Crime
Congress yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali3. Conference of Parties dari UNTOC, termasuk intergovernmental working groups
yang diselenggarakan dalam kerangka UNTOC4. Conference of State Parties dari UNCAC, termasuk intergovernmental working
groups yang diselenggarakan dalam kerangka UNCAC.
76
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 76 7/10/12 2:12 PM

Fenomena Praktik Kejahatan Lintas Negara
Perdagangan NarkobaFenomena angka pertumbuhan kasus Narkoba cenderung meningkat tiap tahunnya.
Misalnya Thailand, dari 112.119 kasus pada tahun 1994 naik menjadi 167.039 kasus di
tahun 1998. Kamboja pada tahun 1994 hanya 32 kasus sementara tahun 1998 menjadi 98
kasus, Malaysia ada 11.672 pecandu pada tahun 1994 mengalami peningkatan menjadi
21.073 di tahun 1998, sementara di Brunei Darussalam yang di tahun 1988 hanya
memiliki 15 kasus, kemudian di tahun 1998, sudah mencapai 423 kasus. Sedangkan
di Indonesia, pertumbuhannya naik 91,33 % (dari 958 perkara di tahun 1994 sampai
1.833 kasus di tahun 1998 meningkat menjadi 3.478 kasus di tahun 2000 yang berarti
meningkat kembali 92 % 27.
Asia Tenggara dikenal sebagai wilayah penghasil obat-obatan terlarang terbesar di
dunia, atau bersama-sama dengan Golden Crescent (Afghanistan, Pakistan, dan Iran),
dan Kolombia, melalui keberadaan segitiga emas di perbatasan Thailand, Myanmar,
dan Laos. Diketahui bersama bahwa Golden Triangle merupakan penghasil 60 %
opium dan heroin dunia. Namun bukan hanya menjadi pemasok opium yang besar
tapi dengan jumlah populasi Asia Tenggara yang cukup besar, maka kawasan ini juga
menjadi pasar yang sangat potensial. Dalam menanggulangi kasus ini, ASEAN telah
mengambil langkah-langkah guna memberantas atau mengurangi tindak kejahatan
ini. Declaration of ASEAN concord, pada tanggal 24 Februari 1976 telah menyepakati
perlunya peningkatan kerjasama dengan lembaga internasional yang relevan guna
memberantas penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Sementara dalam KTT ASEAN
yang ke-5 di Bangkok, Thailand pada Desember 1995, para pemimpin ASEAN
menyerukan perlunya penguatan kerjasama untuk menciptakan “a drug free ASEAN”.
Kelanjutan dari upaya ASEAN dalam mengurangi penyebaran tindak kejahatan ini
adalah melalui KTT informal ASEAN yang kedua di Kuala Lumpur pada Desember
1997, yang mengesahkan dokumen ASEAN vision 2020.
Pembajakan LautData yang pernah dikeluarkan oleh International Maritime Organization (IMO)
menunjukkan bahwa pembajakan dan perompakan bersenjata telah terjadi di berbagai
27 Sumber data ini berasal dari tulisan Abdurrachman Mattalitti, dkk. (2001) “Kerjasama ASEAN dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara” yang diunduh melalui : http://fleepzfloopz.blog.com /2011/05/10/posisi-indonesia-menangani-kejahatan-transnasional-dalam-kerangka-kerjasama-ASEAN/.
77
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 77 7/11/12 12:34 PM

belahan dunia, meliputi Selat Malaka, Samudera Hindia, Afrika Timur, Amerika Selatan, Afrika Barat, wilayah Mediterania dan Laut Hitam, serta Laut Cina Selatan, di mana Laut Cina Selatan adalah wilayah dengan angka pembajakan tertinggi di dunia. International Maritime Bureau (IMB) Kuala Lumpur mengindikasikan bahwa pada tahun 1999 terdapat 285 kasus pembajakan dan perompakan di perairan Asia, 113 di antaranya terjadi di Indonesia, sementara di tahun 2000 terjadi peningkatan dengan terjadinya 117 kasus yang merupakan angka tertinggi di dunia. Data tersebut sempat membuat perairan Indonesia dijuluki The most dangerous waters in the world. Namun dengan operasi laut terkoordinasi antara Indonesia, Malaysia dan Singapura, maka angka tersebut berhasil diturunkan secara signifikan hingga tahun 2011. Dari data yang dikeluarkan oleh IMO menunjukkan bahwa pembajakan dan perompakan bersenjata telah terjadi di berbagai daerah di dunia yang dapat dikelompokkan meliputi selat Malaka, Samudera Hindia, Afrika Timur, Afrika Barat, Amerika Selatan, Laut Mediterania dan Laut Hitam, serta Laut Cina Selatan.
Woman and Children TraffickingPBB telah memasukkan masalah perdangangan gelap wanita dan anak-anak sebagai salah satu kejahatan lintas negara yang tercantum dalam United Nation Convention Againts Transnational Organized Crime yang diadopsi oleh PBB pada tanggal 2 November 2000. Indonesia adalah salah satu negara yang telah menandatangani konvensi tersebut beserta dua protokolnya (Protocol prevent, suppress and punish Trafficking in persons, especially women and children dan protocol against The Smuggling of Migrants by land, sea, and air) karena itu berkewajiban untuk mengimplementasikan konvensi tersebut dalam hukum nasional Indonesia. Indonesia juga telah menandatangani Manila Declaration on Prevention and Control of Transnational Crime di Manila pada tanggal 25 Maret 1998. Dalam menanggulangi kasus Woman and children trafficking ini langkah-langkah yang dilakukan Indonesia adalah dengan mengadopsi UN Convention Againts Transnational Organized Crime beserta dua protokol ke dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah lainnya. Dalam hal itu ASEAN yang berkomitmen untuk menanggulangi berbagai kejahatan lintas negara di ASEAN, termasuk perdagangan perempuan dan anak-anak terus mengupayakan pertukaran informasi, kerjasama di bidang hukum, pengembangan kapasitas kelembagaan, serta kerjasama yang lebih erat dengan negara-negara mitra wacana.
78
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 78 7/10/12 2:12 PM

Penyelundupan SenjataDalam mengatasi kasus penyelundupan senjata di kawasan Asia Tenggara tidak terlepas dari adanya beberapa konflik internal dan gerakan separatisme di berbagai negara, antara lain Kamboja, Filiphina, Myanmar, Thailand, dan Indonesia. Hal ini terjadi karena dipicu oleh adanya control dan peraturan ketat terhadap ijin perdagangan senjata yang dikenakan oleh produsen senjata di negara-negara maju terhadap konsumen senjata yang dikenakan oleh produsen senjata di negara-negara berkembang seperti negara-negara di ASEAN. Dalam menangani kasus ini, ASEAN telah berupaya untuk melakukan pertukaran informasi, masalah hukum, penegakan hukum, pelatihan, pembentukan kapasitas kelembagaan dan kerjasama yang ada seperti ASEAN Senior Officials atau Ministerial Meeting on Transnational Crime.
TerorismeDalam tingkat internasional dengan dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB No. S/Res/1368 dan S/Res/1373, secara tegas dicantumkan upaya memerangi terorisme internasional perlu melibatkan PBB. Ada 12 konvensi internasional dalam pencegahan dan penindakan terhadap terorisme internasional. Indonesia baru meratifikasi 3 konvensi, yaitu Convention of Offences and Certain Other Acts Commited on Board Aircraft (Tokyo convention-1963), Convention for The Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft (The Hague Convention-1970), dan Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation (Montreal Convention-1971). Ini kemudian diadopsi ke dalam hukum nasional, yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 1976. Indonesia juga telah menandatangani 1 konvensi lagi yaitu International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (1999).
Kejahatan lintas negara harus segera ditangani mengingat ini bisa berdampak pada penurunan keamanan, berpotensi mengancam stabilitas negara, dan ketentraman masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi kejahatan lintas negara yang terorganisasi dan sudah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan. Dengan maraknya kejahatan-kejahatan tersebut khususnya di kawasan Asia Tenggara, negara-negara anggota ASEAN kembali menyelenggarakan rangkaian pertemuan Senior Official Meeting on Transnational Crime (SOMTC) ke-10, yang diselenggarakan di Makati, Manila, Filipina, pada tanggal 25-29 Oktober 2010. Ada 8 isu utama terkait terkait kejahatan lintas negara yang dibahas dalam rangkaian pertemuan ini adalah counter terrorism, trafficking in persons, money laundering, arms smuggling, sea piracy, international economic crimes, cyber crime, dan illicit drugs trafficking.
79
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 79 7/10/12 2:12 PM

Indonesia bertindak sebagai pengarah utama (lead shepherd) untuk isu counter terrorism. Selain itu, dalam rangkaian pertemuan tersebut, negara-negara ASEAN juga mencoba untuk terus memperkuat kerjasama yang sudah terjalin dengan baik selama ini dengan negara-negara mitra yaitu Cina, Jepang, Korea Selatan, AS, Rusia, Selandia Baru, dan Australia, dalam menangani isu kejahatan lintas negara yang tengah menjadi perhatian serius berbagai negara ini.
Ancaman kejahatan lintas negara juga memicu transformasi militer karena domain militer terhadap keamanan nasional. Semua negara harus melakukan perubahan doktrin dan organisasi untuk bisa melakukan operasi militer menghadapi kejahatan tersebut bersama pihak Kepolisian masing-masing negara. Operasi militer yang bersifat terbuka untuk bekerjasama dengan berbagai pihak non militer juga “memaksa” perubahan nilai dan budaya di kalangan para perwira militer. Perubahan tersebut meliputi adopsi nilai-nilai dan budaya militer negara lain ke dalam nilai dan budaya negara sendiri sehingga melahirkan integrasi sosial di kalangan militer yang memiliki kepentingan bersama menghadapi ancaman kejahatan tersebut.
3.6. Rangkuman
Revolusi dalam urusan kemiliteran (RMA), atau yang sebelumnya pada masa Perang Dingin oleh blok Timur disebut sebagai revolusi teknik militer (MTR) adalah konsekuensi logis dari transformasi militer AS dan Uni Sovyet. Meskipun secara umum RMA diidentikkan dengan persoalan ancaman terhadap keamanan nasional negara-negara yang ada di dunia dan bukan hanya karena persaingan antara AS dan Uni Sovyet pada masa Perang Dingin, tetapi fakta mengenai sumber dari mana modernisasi Alutsista itu berasal, membuktikan bahwa, selain demi efektivitas dan efisiensi dalam peperangan yang semakin hari semakin sarat dengan nilai-nilai non perang (seperti persoalan kemanusiaan dalam situasi perang), modernisasi Alutsista di dua negara besar itu didukung oleh industri persenjataan mereka yang terus menerus memproduksi peralatan yang tidak saja cukup digunakan di dalam negeri, melainkan juga seperti biasanya, membutuhkan pasar yang lebih luas guna mengahadapi over production atau kelebihan produksi. Ini adalah satu ciri klasik dari kapitalisme yang selanjutnya adalah mencari pasar-pasar baru yang lebih prospektif sehingga mereka bisa terus melakukan modernisasi dan inovasi baru. Demikianlah RMA sesungguhnya bisa dilihat dan dimaknai lebih jauh.
80
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 80 7/10/12 2:12 PM

Mengapa dalam bagian ini juga digambarkan mengenai persoalan-persoalan terkini dari keamanan nasional, seperti konflik-konflik yang terjadi dan TOC yang melampaui batas-batas negara adalah dalam rangka memberikan satu gambaran bahwa perkembangan persenjataan canggih juga berjalan beriringan dengan modernisasi dan “kecanggihan” tindakan kejahatan itu sendiri. Terlepas mana yang lebih dahulu, seperti perdebatan mana yang lebih dulu antara telur dan ayam, tetapi yang paling penting adalah keduanya mengalami perkembangan yang cukup signifikan, baik persenjataan maupun bentuk-bentuk kejahatan lintas negara. Kita bisa saksikan dengan jelas, keberadaan senjata modern dan canggih yang dilahirkan oleh gelombang RMA juga dimanfaatkan secara baik oleh kelompok-kelompok terorisme di dunia, baik yang berlatar belakang agama maupun yang lainnya.
Dengan kondisi tersebut kita bisa menilai bahwa telah terjadi dialektika yang cukup kuat atau ada relasi yang cukup kuat antara produsen persenjataan canggih di negara maju dengan “kecanggihan” dari tindakan pelaku kejahatan. Barangkali secara naif kita bisa katakan modernisasi tindakan dan cara para penjahat dalam melakukan kejahatannya adalah dampak tak diinginkan dari RMA itu sendiri. Kendati pada level empiris, hal itu bisa juga dilihat sebagai salah satu upaya produsen persenjataan canggih dalam memperluas pasar bagi produksi mereka. Dalam hal ini analisis yang mengatakan bahwa RMA lahir dari tantangan yang semakin nyata dalam mempertahankan keamanan nasional di era global, menjadi problematik. Karena secara empiris, kemajuan teknologi perang selalu membutuhkan medan uji yang bisa membuktikan seberapa canggih suatu senjata. Dengan kata lain, keduanya berada pada satu posisi yang setara, sehingga bisa saling mempengaruhi satu sama lain.
Pola konflik yang seolah mencerminkan satu siklus yang terus berputar barangkali bisa dilihat sebagai satu bentuk perubahan sosial yang sifatnya siklikal atau mengulang, namun dalam setiap fasenya, terdapat dinamika interaksi yang tinggi yang mencerminkan secara jelas konteks strategis yang melatari setiap fase perubahan. Penjelasan itu bersumber dari adanya fakta bahwa pola-pola konflik yang berkembang saat ini, dari mulai yang bersifat multipolar, bipolar, unipolar sampai kemudian multipolar lagi, dan ke depan ada kemungkinan untuk menuju pada bipolar (AS dan Cina) berlangsung dengan beragam konsekuensi. Oleh karena itu, penting juga untuk melihat sejauh mana perubahan itu berimbas pada tataran paling empiris dari institusi militer suatu negara. Dengan memperhatikan secara seksama perkembangan konstelasi ekonomi politik global, paling tidak kita bisa melihat arah maupun kecenderungan yang mungkin muncul, sehingga proses transformasi militer nasional juga dilengkapi dengan analisis
81
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 81 7/10/12 2:12 PM

atas kebutuhan-kebutuhan dalam rangka merespon perkembangan situasi keamanan global itu sendiri.
Dari pembahasan tersebut, kita juga bisa menyaksikan bahwa ancaman dan tantangan bagi keamanan nasional saat ini begitu kompleks. Di satu sisi permasalahan-permasalahan klasik yang sejak peradaban manusia ini ada, masih tetap menjadi salah satu faktor kalkulasi para pengambil kebijakan dalam urusan keamanan nasional. Contoh bahwa masih saja ada konflik-konflik antar negara yang dipicu oleh sengketa tata batas negara, kemudian perebutan sumber daya alam terutama energi (energy security) dan pangan (food security), rebutan pengaruh politik internasional, menunjukkan bahwa sebagai sebuah peradaban, manusia tidak pernah lepas dari hasratnya untuk menguasai secara lebih. Manusia juga masih tetap terganggu apabila tempat tinggalnya diusik atau dimasuki tanpa permisi oleh orang lain. Inilah soal klasik yang tetap relevan dimasukkan sebagai hitung-hitungan dalam mencermati ancaman keamanan nasional.
Namun begitu, kompleksitas persoalan keamanan nasional kontemporer dilengkapi dengan semakin canggihnya bentuk-bentuk kejahatan transnasional. Bahwa kejahatan bukan hal baru, itu benar, tetapi kejahatan yang bisa bertransformasi secara efektif dengan memanfaatkan kecanggihan perangkat persenjataan hasil dari RMA menjadi sesuatu yang dianggap baru bagi sebagian kalangan. Kebaruan-kebaruan dalam tindakan teorisme, perdagangan narkotika, penjualan anak-anak dan perempuan, penyelundupan senjata dan perompakan membuat sebagain kalangan terkaget-kaget dalam mengantisipasi kenyataan tersebut. Inilah yang dikatakan oleh beberapa sarjana bahwa institusi keamanan negara cenderung tidak siap dengan pola-pola antisipasi terhadap hal ini. Mereka mungkin memiliki kesigapan dalam menghalau setiap potensi ancaman klasik seperti yang telah disebutkan dalam bahasan sebelumnya, tetapi mereka mengalami kesulitan untuk mengantisipasi jenis-jenis kejahatan transformatif ini.
Dengan bentuk-bentuk kejahatan transnasional yang telah bertransformasi itu, tentu saja dibutuhkan pendekatan super berbeda dengan pendekatan sebelumnya. Jika pendekatan sebelumnya ancaman itu menjadi otoritas nasional dan hanya bisa direspon oleh otoritas nasional karena menyangkut tata batas dan penguasaan aset sumber daya alam, maka untuk jenis ancaman kejahatan terorganisir, dibutuhkan pendekatan yang mengedepankan kerjasama dan koordinasi antar negara. Sebagian kalangan menilai pendekatan multistate centric adalah satu-satunya jalan agar antisipasi terhadap hal ini bisa secara efektif dilakukan. Pertanyaannya kemudian, apa memang sedemikian vitalnya pendekatan multistate centric dalam konteks mengantisipasi bentuk-bentuk kejahatan baru ini?
82
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 82 7/10/12 2:12 PM

Pendekatan multistate centric mensyaratkan kerjasama dan koordinasi yang terorganisir dengan negara-negara lain. Dengan melakukan patroli bersama dan penjagaan kawasan secara bersama-sama, hal itu bisa lebih mengefektifkan antisipasi sehingga ada upaya preventif untuk bisa mencegah niat-niat dari tindakan kejahatan yang dimaksud. Tetapi, dalam konteks pendekatan ini, pertanyaan yang kemudian timbul, seberapa besar wewenang otoritas bersama itu untuk bisa melakukan proses intervensi di satu kawasan atau teritorial sebuah negara. Sejauh mana pula, pendefinisian atas kedaulatan suatu negara mesti direvisi dengan cara pandang seperti itu. Bagi negara kepulauan seperti Indonesia yang penjagaan atas kawasannya masih belum didukung oleh peralatan yang optimal, terutama kawasan lautnya, sejauh mana kita bisa mentolerir upaya negara-negara kawasan untuk bisa melakukan intervensi di dalam perairan teritorial Indonesia. Begitu juga sebaliknya, sejauh mana kita bisa menindak atau melakukan upaya perburuan ketika pelaku kejahatan itu masuk ke dalam teritori negara tetangga. Maksimal yang bisa dilakukan adalah fungsi koordinasi dan bukan intervensi secara langsung. Proses intervensi atas sebuah kejahatan, sekali lagi hanya bisa dilakukan oleh aparat yang berwenang di negara tersebut. Akan terlalu riskan apabila aparat keamanan negara lain masuk ke dalam kawasan sebuah negara yang berdaulat. Kiranya, saat ini masih menjadi problematika dari pendekatan multistate centric.
Apa yang dijabarkan di atas adalah sebuah argumen teoritik yang secara kritis melihat pendekatan multistate centric dalam menyelesaikan persoalan kejahatan transnasional. Secara empirik, sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan melakukan operasi militer pembebasan M.V. Sinar Kudus dari perompak Somalia pada tahun 2011 menjadi semacam bahan pembelajaran bukan saja bagi Indonesia, tetapi juga bagi negara-negara yang selama ini meyakini bahwa hanya dengan operasi militer gabungan kejahatan itu bisa ditanggulangi. Praktik penyelesaian masalah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ketika “membereskan” para perompak itu menjadi kritik paling kongkrit atas teori-teori hubungan internasional multistate centric.
Meskipun penuh problematika, kiranya pendekatan itu bukan tidak berarti sama sekali. Merancang sebuah proses kerjasama regional yang dilandasi oleh semangat sinergi dan penghargaan atas kedaulatan setiap negara bisa melahirkan satu kerangka konsep kerjasama militer regional yang memang pas dengan kebutuhan kawasan. Pokok pikiran paling penting dari penjelasan di atas adalah kerja bersama dalam pemberantasan kejahatan transnasional terorganisir mesti dirancang dengan area kerja yang spesifik sehingga setiap pihak mengerti peran dan posisinya, terutama ketika terkait dengan masalah kedaulatan sebuah negara bangsa.
83
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 83 7/10/12 2:12 PM

84
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 84 7/10/12 2:12 PM

Bab IV
Transformasi Militer - StudiBeberapa Negara• Perubahan Paradigma Peperangan• Praktik Transformasi Militer di Eropa• Pengalaman Transformasi Militer di Asia• Perbandingan Kasus Transformasi Militer Cina dan Amerika Serikat• Rangkuman
85
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 85 7/10/12 2:12 PM

Bab IV. Transformasi Militer - Studi Beberapa NegaraMengapa transformasi militer negara-negara menjadi penting untuk dibahas dalam buku ini? Pertanyaan itu adalah salah satu upaya bagi kita untuk bisa memberikan semacam petunjuk bagaimana sesungguhnya transformasi militer itu tidak terlepas dari hiruk pikuk globalisasi yang menyentuh persoalan-persoalan mendasar masyarakat di dunia, termasuk di dalamnya gagasan mengenai Revolutionary in Military Affairs dan Military Technology Revolution yang berasal dari Barat “menulari” banyak negara-negara di dunia. Dalam penularannya itu, ada kelompok-kelompok negara yang kemudian mengikuti secara massif aspek-aspek perubahan yang disyaratkan, namun ada juga yang melakukan inovasi atau penyesuaian dengan situasi dan kondisi negara mereka. Selanjutnya, dalam proses transformasi tersebut, biasanya ada alasan-alasan yang sangat mendasar terkait dengan kepentingan keamanan nasional tiap negara, aspek-aspek transformasi yang dilakukan, pihak-pihak yang memiliki peranan dalam proses transformasi itu, sistem dan struktur yang mendukung terjadinya proses transformasi, termasuk aliansi-aliansi strategis yang terlibat dalam setiap proses transformasi militer mereka.
4.1. Perubahan Paradigma Peperangan
Layaknya cara manusia untuk bisa bertahan hidup, pada dasarnya demikianlah perang dipandang dan dilihat sepanjang peradaban manusia. Pada penjelasan-penjelasan yang lebih klasik, seperti yang telah dikemukakan oleh Von Clausewitz, perang dikatakan sebagai satu mekanisme lanjutan dari proses politik, karena manusia adalah mahkluk ekonomi, sekaligus mahkluk politik. Perang adalah upaya terakhir manusia untuk mempertahankan hidup mereka melalui tindakan kekerasan secara massal yang melibatkan kekuatan militer dalam jumlah tertentu. Dalam penjelasan yang lain, Thomas Lindemann (2010) dalam Causes of War: the Struggle for Recognition, mengungkapkan bahwa dalam perang, pihak militer berperan sangat penting dalam menentukan tujuan, arah, strategi, operasi, taktik, dan itu merupakan
86
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 86 7/10/12 2:12 PM

arena yang dilakukan dalam menunjang apa yang dinamakan keamanan nasional. Bagaimanapun juga, tujuan dari kerja keras dan perjuangan dalam perang ini adalah untuk mendapatkan pengakuan, terutama pengakuan secara politik, baik itu dengan alasan keberlanjutan maupun keamanan nasional.
Perang juga membutuhkan simbol, dan simbol itulah yang dipakai oleh negara atau beberapa negara yang bekerjasama, atau kerjasama antar-negara dengan tujuan menaklukan negara lain atau menguasai negara lain dengan berbagai cara. Alasan ekonomi dan politik menjadi penting dalam penentuan kerjasama tersebut. Demikian juga alasan penguasaan sumber daya dalam rangka menjaga apa yang namanya keberlanjutan itu. Jadi manusia sebagai makhluk ekonomi dan juga makhluk politik akan memberikan pilihan yang rasional, apakah ia memutuskan akan ikut perang atau meninggalkan perang. Adanya pemikiran lain yang juga mengatakan bahwa apabila segala sumber daya terdistribusi dengan baik, maka kemungkinan perang akan kecil, namun di lain pihak adanya perang juga disebabkan karena adanya keinginan mendominasi dan menghegemoni yang lain.
Hal lain yang juga dibutuhkan dalam berbagai kerjasama adalah adanya kolektifitas simbol, karena dengan adanya simbol kolektif itu jiwa patriotisme dan semangat akan bangkit untuk membela simbol tersebut dalam bentuk semangat bela negara atau nasionalisme. Selain itu akan dibuat juga berbagai kebijakan berdasarkan kolektifitas tersebut yang tentunya akan menguntungkan negara-negara yang bergabung di dalam kolektif simbol itu.
Pada tahap menentukan posisi atau pilihan inilah pengakuan secara politik terhadap negara-negara yang tergabung dalam kolektif simbol itu sangat penting, karena negara yang tergabung dalam satu simbol itulah yang akan memberikan pilihan kepada negara lain untuk memberikan posisinya atau menjelaskan posisinya terhadap mereka ketika mereka menyatakan perang. Untuk itu, negara yang belum tergabung dalam apa yang namanya kolektifitas simbol harus memilih dan menentukan posisinya.
Karena perang adalah salah satu cara manusia atau masyarakat untuk mempertahankan hidupnya, konsekuensi yang paling sederhana adalah kenyataan bahwa mekanisme tersebut bisa dipastikan bersifat fleksibel ataupun relatif dinamis karena karakteristik manusia itu sendiri pada dasarnya dinamis. Begitu pula dengan perang dan peperangan, jika ditilik dari perkembangannya, peperangan sampai saat ini telah mengalami lima kali lompatan. Berikut adalah penjelasannya:
87
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 87 7/10/12 2:12 PM

• Peperangan Generasi Pertama. Di sini yang terjadi adalah peperangan dengan cara yang massif dan diikuti oleh banyak orang. Alat perang yang digunakan pada saat itu masih menggunakan senjata sederhana, seperti parang, tombak ataupun perisai, misalnya pada Perang Yunani kuno ataupun Perang Salib. Pihak yang menang biasanya adalah mereka yang memiliki jumlah prajurit perang dan senjata yang paling banyak.
• Peperangan Generasi Kedua. Meskipun peperangan ini masih seperti generasi pertama, tetapi dalam peperangan generasi kedua sudah ada kemajuan teknologi, yaitu sudah digunakannya meriam, senapan dan pistol. Cara berperangnya masih massif misalnya Perang Sipil di AS. Pada peperangan generasi kedua masih belum ada taktik dalam medan tempur.
• Peperangan Generasi Ketiga. Peperangan ini berbeda dengan generasi pertama dan kedua. Karena pada generasi ketiga sudah tidak massif lagi, tetapi lebih mengutamakan teknologi dan sudah ada taktik. Bahkan pada skala besar sudah diterapkan strategi tempur, seperti pada Perang Dunia Kesatu dan Kedua, serta selanjutnya pada era Perang Dingin dan pasca Perang Dingin.28
• Peperangan Generasi Keempat. Sejak peristiwa 11 September 2001 lahirlah generasi keempat. Peperangan pada generasi ini disebut juga peperangan asimetris (assymmetric warfare) karena terjadi antara aktor negara dan aktor non negara. Jadi di sini yang terjadi adalah negara berperang dengan kelompok-kelompok tertentu bukan negara seperti peperangan dari negara melawan organisasi kejahatan transnasional. Atau teroris yang masuk ke dalam jaringan kejahatan lintas negara, sehingga mendorong negara untuk berperang melawan teror.
• Peperangan Generasi Kelima. Peperangan dalam pengertian generasi kelima beranjak dari peperangan generasi keempat, yakni peperangan yang melibatkan aktor negara melawan aktor non negara. Namun demikian, yang menjadi pembeda adalah keterlibatan dari kelompok terorisme yang menjadi musuh negara dalam kegiatan atau tindakan kriminal. Maksudnya adalah teroris sekaligus melakukan kegiatan kriminal guna mencapai tujuan-tujuan yang mereka rencanakan. Generasi kelima juga ditandai dengan munculnya information warfare, cyber warfare, dan lain-lain. 29
28 Peperangan dari generasi pertama sampai ketiga masih bersifat simetris, dalam pengertian terjadi peperangan antara aktor negara vs negara.29 Teroris biasanya mendapatkan biaya dari para simpatisan atau para pendukungnya, atau biaya sendiri. Apa yang terjadi sekarang adalah semua negara telah bergabung untuk melawan terorisme dengan cara memotong semua kemungkinan aliran dana kepada teroris, misalnya memotong jalur keuangan atau pembiayaannya. Tindakan yang paling utama adalah menyumbat aliran dana, misalnya bantuan dari suatu negara tertentu untuk alasan bantuan kegiatan agama tertentu, diberhentikan karena terindikasi disalah-gunakan untuk kegiatan teroris. Tersumbatnya sumber daya finansial kelompok teroris memicu mereka melakukan tindakan kriminal untuk memperoleh dana.
88
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 88 7/10/12 2:12 PM

4.2.
Praktik Transformasi Militer di Eropa
Pada bagian ini akan dibahas transformasi militer di beberapa negara Eropa seperti Jerman, Inggris, Rusia dan Kanada dari Amerika Utara. Pemilihan dari beberapa negara ini didasarkan dari beberapa karakteristik seperti dalam hal kapasitas kekuatan militer mereka yang relatif sama. Walaupun mengalami sejarah pergolakan militer yang berbeda, organisasi militer mereka relatif mapan sekarang ini. Dengan memperbandingkan kasus-kasus transformasi militer di beberapa negara Eropa dan Kanada ini kita dapat melihat kecenderungan faktor penyebab utama transformasi tersebut, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Dan bagaimana relevansi faktor tersebut terhadap perubahan institusi militer mereka.
Transformasi militer Kanada mengalami perubahan yang cepat, baik dalam hal struktur maupun kapasitasnya, dimulai dari tahun 2003. Proses transformasi dimulai dari perubahan ide mengenai peran militer Kanada dari sebuah institusi penjaga perdamaian menjadi institusi perang yang siap untuk bertempur (Dan Fitzsimmons, 2009) karena para pengambil kebijakan di Kanada menyadari bahwa konflik dalam era modern sangat dinamis. Contohnya ketika terjadi penyerangan 11 September 2001.
Kebijakan mengenai peran militer Kanada sebagai sebuah institusi penjaga perdamaian dikenal pada masa pemerintahan Perdana Menteri Jean Chretein (1993-2003). Hal ini berdampak pada institusi militer Kanada. Militer Kanada distrukturkan untuk merefleksikan kebijakan ini. Militer Kanada bersifat pasif, patroli pun ditujukan bukan untuk bertempur. Kebijakan ini terefleksi dari komitmen Kanada untuk menjaga perdamaian di Balkan, Kosovo dan sebagainya. Konsekuensi dari kebijakan ini juga menyangkut pengurangan pembelian senjata seperti tank yang berjumlah 114 pada tahun 1990 menjadi 66 pada tahun 2000.
Sebaliknya kebijakan Perdana Menteri Paul Martin (2003-2006) mengambil posisi bahwa militer Kanada merupakan sebuah institusi perang yang siap untuk bertempur. Jika kita kaji perubahan ini merupakan suatu perubahan yang radikal dalam struktur dan kapasitasnya. Struktur militer Kanada menjadi lebih nyata (tangible). Militer Kanada dibentuk untuk siap berpartisipasi dalam misi memberantas jaringan teroris dan negara-negara yang menyembunyikan atau melindungi mereka. Transformasi ini juga meliputi peningkatan unit-unit pertahanan dan penyerangan, baik dalam jumlah personel maupun persenjataan. Transformasi ini merupakan proses yang panjang menuju sebuah institusi militer Kanada yang mampu dalam operasi pemberantasan
89
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 89 7/10/12 2:12 PM

(teroris) sehingga menempatkan Kanada sebagai negara garis depan. Perubahan strukturpun dibentuk menuju struktur yang lebih efektif dengan meningkatkan kapasitas personel dan persenjataan yang memiliki mobilitas tinggi, termasuk juga persenjataan yang canggih (dalam hal penentuan keakuratan) untuk Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Sehingga operasi militer di luar negara Kanada nantinya dapat berjalan secara efisien. Hal ini mendorong Kanada untuk memiliki sendiri persenjataan-persenjataan tersebut yang dalam kebijakan sebelumnya hal ini tidak dianggap sebagai kebutuhan yang mendesak. Dan biasanya jika melakukan operasi militer, militer Kanada akan bekerjasama dalam hal penggunaan fasilitas militer dengan militer AS atau negara lainnya. Walaupun kebijakan ini dianggap agak riskan tetapi Jean Chretein menggangap kondisi ini masih merupakan kondisi yang “normal” ketika Kanada berperan sebagai penjaga perdamaian.
Perubahan dalam institusi militer Kanada distrukturkan untuk membentuk operasi-operasi khusus dalam wilayah musuh (luar negeri). Operasi khusus, termasuk juga pengintaian, perang yang tidak konvensional, melawan aksi teroris, dan sebagainya. Operasi-operasi ini ditujukan untuk melakukan intervensi di negara lain, termasuk juga “pertempuran perang yang terbatas”.
Berdasarkan kajian di atas, proses transformasi institusi militer Kanada merupakan suatu rangkaian dalam proses demokratisasi. Faktor yang sangat penting dan sangat kuat untuk mendorong transformasi ini adalah perubahan yang radikal tentang bagaimana para pengambil kebijakan (politik) menentukan peran institusi militer mereka dalam dunia internasional. Contoh, apakah suatu negara ingin menjadi sebagai pemimpin dunia, mediator dan konsiliator yang netral, dan sebagainya, ternyata sangat ditentukan oleh kapasitas elite negara.
Sementara itu, transformasi militer Jerman yang dimulai pada tahun 1990 dominan ditentukan oleh faktor eksternal atau yang kita sebut sebagai tekanan dari dunia internasional (Dirk Steinhoff, 2011). Jika tidak ada tekanan dari dunia internasional untuk bergabung menjadi salah satu negara yang aktif untuk menjaga keamanan dunia, Jerman enggan untuk melakukan transformasi militer mereka dari bentuk Bundeshwer ke pasukan sukarela (volunteer) penjaga perdamaian dunia. Dalam hal ini, peran NATO dan EU sangat signifikan.
Militer Jerman mempunyai pengalaman beberapa kali dalam meningkatkan kompetensi dan perannya di antara negara-negara Eropa setelah terjadinya penyatuan Jerman. Beberapa perang besar mengakibatkan suatu trauma besar bagi rakyat Jerman, sehingga militer Jerman yang cenderung mengambil posisi yang pasif terhadap
90
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 90 7/10/12 2:12 PM

perkembangan keamanan dunia. Rakyat Jerman mengumandangkan adagium tidak akan berperang lagi. Sikap ini sebenarnya merupakan refleksi dari trauma rakyat Jerman terhadap perang-perang tersebut. Dan akibatnya Jerman mengalami krisis atau lebih tepatnya mengalami defisit sehingga anggaran untuk militer mereka sangat terbatas sehingga sangat sulit untuk melakukan modernisasi dalam bidang militer.
Walaupun demikian, negara Jerman menyadari bahwa ia tidak bisa melepaskan diri dari relasi dunia internasional. Apalagi menyangkut letak negara Jerman yang strategis dan potensi yang dimiliki oleh militer Jerman juga sangat mumpuni untuk berbagi dalam upaya menjaga keamanan dunia. Tentu saja, negara Jerman juga mempertimbangkan sisi positif jika Jerman bergabung dalam NATO dan EU. Selain berbagi beban untuk menjalankan tugas menjaga keamanan dunia, anggota NATO dan EU juga berbagi sumber daya. Hal ini dapat mengakselerasi modernisasi militer Jerman, baik dalam bidang persenjataan dan peningkatan teknologi komunikasi maupun pengembangan kapasitas personel.
Faktor tekanan dunia internasional memang tidak bisa diabaikan ketika melakukan kajian tentang transformasi militer di beberapa negara, termasuk negara Rusia. Rusia yang dahulunya merupakan salah satu negara yang kuat dan disegani di dunia, namun di pasca Perang Dingin juga melakukan transformasi militer, khususnya dalam hal doktrin (Alexei G. Arbatov, 2000). Militer Rusia setelah Perang Dingin tidak hanya mengalami ancaman dan tantangan dari luar, tetapi juga ancaman yang bersifat internal. Banyak konflik terjadi di Rusia sendiri. Dari luar, AS dan sekutunya berusaha supaya Rusia melepaskan program senjata nuklir mereka. Rusia dalam pandangan negara-negara Barat (AS dan sekutunya) masih merupakan ancaman yang potensial. Di sisi lain, negara-negara Barat berusaha untuk melakukan intervensi terhadap konflik-konflik yang terjadi di dalam negara Rusia. Hal ini tentu saja membuat “ketidak-nyamanan” bagi Rusia. Akan tetapi, Rusia juga tidak bisa menampikkan konsekuensi dari konflik dengan dunia Barat di mana Rusia bisa mengalami embargo dalam bidang ekonomi, politik dan sebagainya. Embargo dapat menyulitkan pertumbuhan perekonomian Rusia yang pada akhirnya akan berdampak pada keamanan negara Rusia.
Untuk merespon berbagai persoalan di atas, maka Rusia melakukan transformasi dalam tubuh militer mereka, khususnya doktrin. Doktrin militer didasarkan atas pencegahan nuklir, peranan militer dalam menangani konflik domestik dan pertahanan konvensional yang kuat. Dengan perubahan doktrin ini, Rusia bahkan mulai mengambil bagian untuk menjaga perdamaian dunia. Dampak dari negosiasi ini, hubungan politik dan ekonomi mulai terbuka untuk Rusia walaupun dalam realitasnya kerjasama Rusia
91
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 91 7/10/12 2:12 PM

dengan negara-negara Barat masih setengah hati. Perlu upaya dan proses yang panjang untuk melakukan terwujudnya integrasi militer Rusia dan Barat dalam misi untuk menjaga perdamaian dunia tersebut, termasuk pemberantasan teroris.
Jika pada pembahasan sebelumnya kecenderungan perubahan institusi militer dipengaruhi oleh tekanan dari dunia internasional untuk berpartisipasi dalam menjaga perdamaian dunia dan penegakan nilai-nilai demokrasi, lantas bagaimana dengan yang menjadi pionir penjaga perdamaian tersebut, misalnya Inggris. Transformasi institusi militer Inggris juga ditujukan kepada pencapaian militer Inggris yang modern (Adam N. Stulberg and Michael D. Salomone, 2007). Institusi militer Inggris distrukturkan kepada peningkatan kapasitas personel, peningkatan senjata yang tingkat keakuratannya sangat tajam dan manajemen unit-unit pasukan khusus. Militer Inggris selalu melakukan evaluasi dalam kerangka ini sehingga institusi militer Inggris dirancang agar semakin efektif dan efisien dalam merespon ancaman dunia yang semakin kompleks misalnya operasi pemberantasan jaringan teroris ataupun ancaman pengembangan teknologi nuklir illegal.
4.3.
Pengalaman Transformasi Militer di Asia
JepangAliansi AS-Jepang dimulai dengan pendudukan AS atas Jepang setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Selanjutnya AS menyediakan platform dan rencana untuk kesiapan militernya di Asia. Konstitusi Jepang yang dirancang oleh pejabat AS dan diadopsi oleh legislatif Jepang pada tahun 1947, dan di dalam pasal 9 sesungguhnya mengatakan bahwa: “Angkatan Darat, Laut, Udara dan potensi perang lainnya tidak boleh dibentuk.” Namun hal tersebut mengalami perubahan setelah terjadi konfrontasi dengan Uni Sovyet, di mana tujuan dari pendudukan terhadap Jepang bergeser yaitu dengan membangun Jepang sebagai benteng strategis terhadap ancaman komunis. 30
Setelah pecah Perang Korea tahun 1950, AS menekan agar dibentuk angkatan bersenjata nasional Jepang, dan pada tahun 1954 terbentuklah Pasukan Bela-Diri atau Self-Defense Forces (SDF). Perdebatan tentang SDF, yang dalam praktiknya berkembang menjadi militer yang didanai dan dilengkapi dengan baik ternyata melanggar pasal 9 di atas dan terus berlangsung sampai hari ini. Jepang berdaulat pada tahun 1952
30 Emma Chanlett-Avery, Specialist in Asia Affairs, 18 January 2011. Congressional Research Service. Diunduh dari : http://www.crs.gov.
92
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 92 7/10/12 2:12 PM

setelah penandatanganan San Francisco Peace Treaty, yang secara resmi mengakhiri
konflik dan Jepang setuju memberikan kompensasi terhadap kejahatan perang yang
dilakukannya.
Selama Perang Dingin, AS semakin dipandang Jepang sebagai sekutu strategis
untuk melawan ancaman Uni Sovyet di Pasifik. A Mutual Security Assistance Pact tahun 1952 diganti dengan Treaty of Mutual Cooperation and Security tahun 1960, di
mana Jepang mengijinkan militer AS beroperasi di atas wilayahnya dan AS berjanji
untuk melindungi keamanan Jepang. Pada dasarnya Jepang menyerahkan masalah
kebijakan luar negeri dan masalah keamanan ke AS dan Jepang sendiri hanya fokus
pada pembangunan ekonomi dalam negeri.
Banyak yang tidak setuju dengan kontroversi pasal 9 tersebut, bahkan mau merevisi
dan membatalkannya. Salah satunya adalah Perdana Menteri Kishi Nobusuke yang
menegosiasikan revisi traktat 1960 tersebut dengan memobilisasi politik kiri untuk
perubahan. Kishi menghujamkannya lewat parlemen dan ratusan ribu demonstran
turun ke jalan di Tokyo, menyebabkan pembatalan kunjungan oleh Presiden Dwight
Eisenhower dan pengunduran diri Kishi.
Hubungan pertahanan AS-Jepang memasuki masa ketidakpastian antara lain akibat
keputusan yang diambil Presiden AS Richard Nixon yang disebut Guam Doctrine
1969 (sebutan pada sekutu AS untuk memberikan pertahanan pada mereka sendiri?);
normalisasi hubungan antara Cina dan AS; penarikan AS dari Vietnam. Hubungan
tersebut membaik ketika PM Eisaku Sato dan Nixon menandatangani komunike
bersama yang mengembalikan kontrol Pulau Okinawa pada Jepang pada tahun 1972.
Dan pembentukan Security Consultative Committee tahun 1976 sebagai realisasi
peningkatan kerjasama pertahanan dan perencanaan bersama untuk menanggapi
serangan terhadap Jepang.
Pada pasca Perang Dingin, Jepang dikritik komunitas internasional karena
kegagalannya menyediakan bantuan militer langsung kepada koalisi selama Perang
Teluk di Persia pada tahun 1990-1991, meskipun Jepang sudah berkontribusi $13
miliar untuk militer AS dan bantuan kemanusiaan. Dalam perjalanannya, Jepang juga
ikut berpartisipasi dalam Operasi Perdamaian PBB, di mana SDF Jepang dikirim ke
Kamboja, Mozambik, Timor-Timur dan Dataran Tinggi Golan.
Ketegangan atas Korea Utara dan Selat Taiwan berkontribusi terhadap revisi
pedoman pertahanan pada tahun 1996-1997 oleh Presiden Clinton dan PM Ryutaro
Hashimoto. Peluncuran rudal yang dilakukan Korea Utara akhirnya memacu Jepang
juga untuk melakukan penelitian bersama dengan AS untuk membangun sistem
pertahanan rudal balistik.
93
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 93 7/13/12 12:12 PM

Kebijakan AS terhadap Asia Timur di bawah pemerintahan Bush yang mengambil pendekatan pro Jepang sudah jelas sejak awal. Berbagai laporan yang masuk ke pemerintah juga menyerukan agar perlu ditingkatkan kerjasama dengan Jepang dan menjadi mitra yang setara. Respon Jepang terhadap serangan teroris adalah memperkuat hubungan dengan AS dan menjadikannya sebagai mitra luar negeri. Di bawah PM Junichiro Koizumi, legislatif Jepang mengesahkan Undang-Undang Anti Teroris dan memungkinkan Jepang untuk mengirimkan kapal tanker ke Samudera Hindia untuk mendukung operasi militer di Afghanistan.
Pada bulan Februari 2004, Jepang mengirimkan lebih dari 600 personel militer ke Irak untuk membantu kegiatan rekonstruksi dan ini adalah untuk pertama kalinya Jepang mengirimkan tentara ke luar negeri sejak Perang Dunia Kedua, tanpa mandat internasional. Pasukan darat ditarik tahun 2006 dan sebuah divisi SDF Udara Jepang terus bertugas sampai 2008 ketika otoritas PBB untuk pasukan internasional di Irak berakhir. Karena kebijakan itulah yang menyebabkan Koizumi dan LDP yang berkuasa selama 30-40 tahun tumbang dan mengakibatkan PM Jepang naik dan turun hanya dalam hitungan bulan sejak tahun 2008 sampai dengan 2011.
Obama berkuasa tahun 2009 dan terus berhubungan dengan Jepang, walaupun ada beberapa komentator yang melihat bahwa hubungan yang lebih baik antara Washington dengan Beijing akan meminggirkan Tokyo. Ketika DPJ berkuasa di bawah kepemimpinan Yukio Hatoyama, hubungan dengan Washington sedikit menurun akibat perbedaan kepentingan terhadap relokasi pangkalan militer Futenma, dan kebijakan luar negeri DPJ yang condong Asia-Sentris sehingga sebagian pengamat menilai bahwa Tokyo mulai menjauh dari Washington. Setelah berbulan-bulan melakukan musyawarah dengan AS, akhirnya Hatoyama setuju untuk relokasi. Namun kontroversi politik sekitar Futenma memainkan peran dalam pengunduran dirinya pada Juni 2010. Penggantinya, PM Naoto Kan tampak ingin memperbaiki hubungan tersebut dan bersedia menyediakan dana untuk berkontribusi dan membiayai pasukan AS di Jepang.
Berdasarkan Perjanjian Kerjasama dan Keamanan (Treaty of Mutual Cooperation and Security), maka sekitar 53.000 tentara AS ditempatkan di Jepang dan memiliki hak penggunaan eksklusif terhadap 89 fasilitas militer di seluruh Jepang. Sebagai kompensasinya, AS akan menjamin keamanan Jepang dan hubungan ini sudah berjalan lebih dari 50 tahun.
Pada bulan Desember 2010, Jepang mengumumkan bahwa mereka telah mengadopsi pedoman pertahanan baru yaitu National Defense Program Guidelines (NDPG). NDPG
94
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 94 7/10/12 2:12 PM

2010 dibangun berdasarkan versi 2004 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Koizumi yang mempertahankan kebijakan pertahanan yang berorientasi pada kemampuan diri sendiri, namun lebih terintegrasi pada strategi keamanan dan militer yang memanfaatkan “multi-functional flexible defense forces” untuk menangani keamanan perubahan lingkungan.
Kebijakan tersebut juga secara eksplisit menyebutkan tentang perlunya memajukan kerjasama dengan negara lainnya, termasuk Korea Selatan, Australia, India, dan negara-negara ASEAN. Versi 2004 lebih condong ke arah perspektif global yang memandang keamanan Jepang dan kawasan terkait dengan stabilitas internasional, sedangkan pedoman 2010 muncul untuk mengarahkan fokus kembali ke wilayah Asia-Pasifik. Meskipun pedoman menunjukkan sifat keamanan yang selalu berubah, namun pedoman ini juga dapat dinilai resistensi Jepang untuk kembali “normal” menjadi negara militer. Dokumen ini tidak menunjukkan atau menafsirkan ulang pasal 9, dan saat ini keinginan untuk mengubah pertahanan diri kolektif terasa sulit dilakukan karena mengalami kemacetan politik.
SingapuraBeberapa analis militer menilai kemampuan Angkatan Bersenjata Singapura paling maju di Asia Tenggara. Saat ini Singapura memiliki peralatan tempur seperti “standar” NATO dan juga menerapkan standar yang tinggi bagi bintara harus memiliki gelar akademik minimal S-1 dan perwira harus minimal S-2. Membangun Angkatan Bersenjata Singapura dan meningkatkan industri pertahanan nasional, serta pertahanan lokal, termasuk Research and Development mencerminkan tekad pemerintahan Singapura di bawah Partai Aksi Rakyat untuk menjamin kelangsungan hidup city state (negara kota) di lingkungan regional yang berpotensi konflik. Kuncinya dalam beberapa dekade adalah meningkatnya keuntungan ekonomi. Singapura dengan populasi yang relatif berpendidikan tinggi dan diperkuat oleh interaksi yang semakin intens antara angkatan bersenjata dan industri pertahanan negara-negara industri maju. Hal tersebut telah memungkinkan Singapura untuk mulai mengambil keuntungan dari peluang yang ditawarkan oleh RMA. 31
Angkatan Bersenjata Singapura telah mengaplikasikan sistem canggih berupa komando, kontrol, komunikasi dan pengelolaan komputer (Command, Control,
31 Tim Huxley, Senior Fellow for Asia-Pasific Security at the International Institute for Strategic Studies, Defending the Lion City : The Armed Forces of Singapore. Diunduh dari: http://www.mindef.gov.sg/content/imindef/publications/pointer/journals/2004/v30n1/features/feature4.html.
95
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 95 7/10/12 2:12 PM

Communications and Computer/C4), serta intelijen, pengawasan dan pengintaian (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance/ISR). Dukungan logistik terpadu (Integrated Logistic Support/ILS) juga berkembang dengan baik.
Situasi geopolitik telah memaksa pemerintah Singapura untuk mengambil pertahanan yang sangat serius sejak negara kota itu terpisah dari Malaysia pada tahun 1965. Meskipun ukuran dan populasi Singapura kecil, tetapi di akhir 1990-an Angkatan Bersenjatanya menjadi yang terbaik, paling terlatih dan berpotensi paling efektif se-Asia Tenggara. Pemerintah secara rutin menyisihkan 25 s/d 30 % dari total belanja tahunan (sekitar 5 % dari PDB) untuk angkatan bersenjata. Pada 2003 dan 2004, jumlah anggaran pertahanan Singapura sekitar S $ 8.25 miliar (US $ 4.7 miliar).
Dalam mengembangkan angkatan bersenjatanya, para pemimpin Singapura menekankan pemanfaatan teknologi sebagai strategi dan juga sebagai kompensasi karena kurangnya tenaga militer yang profesional. Keunggulan teknologi (technological edge) diberikan untuk Angkatan Bersenjata Singapura dalam menjaga kemungkinan potensi musuh di wilayah terdekatnya. Keunggulan teknologi Singapura berasal dari pembelian peralatan militer canggih dari pemasok luar negeri (misalnya, F-16C/D fighter/strike aircraft dari AS selama dekade 1990-an), juga dari produk industri pertahanan Singapura sendiri sebagai hasil dari meningkatkan upaya Research and Development. Dalam menempatkan pembangunan masa depan Angkatan Bersenjata Singapura, dengan tegas dalam konteks baru tentang Defending Singapore abad 21 (DS 21) berjanji bahwa Angkatan Bersenjata Singapura akan “mengeksploitasi” perkembangan RMA, seperti integrasi teknologi informasi ke dalam sistem senjata untuk mencapai keunggulan medan. Singapura memprioritaskan pembangunan teknologi.
Angkatan Bersenjata Singapura 2000 mengadopsi cetak biru tahun 1988 yang merupakan hasil dari tinjauan struktur kekuatan utama. Ternyata hal ini membawa perubahan yang signifikan bagi organisasi militer Singapura dan doktrin, khususnya tentara. Di bawah Angkatan Darat 2000, turunan tunggal dari Angkatan Bersenjata Singapura 2000, maka tentara diberi doktrin operasi gabungan senjata dan taktik “pertempuran 24-jam”. Angkatan Bersenjata Singapura 2000 juga banyak memberikan penekanan kepada layanan kerjasama. Kementerian Pertahanan Singapura berkomitmen untuk mengeksploitasi informasi baru dan teknologi komunikasi untuk memberikan Angkatan Bersenjata Singapura sebuah “ujung strategis” di lingkup C4 dan ISR.
Tantangan lain untuk Kementerian Pertahanan Singapura dan Angkatan Bersenjata Singapura adalah bagaimana mengembangkan doktrin-doktrin baru dan bentuk-bentuk organisasi yang memungkinkan dilakukan eksploitasi teknologi canggih dengan cara
96
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 96 7/10/12 2:12 PM

yang relevan terkait dengan keadaan strategis negara kota yang sedang berkembang. Lingkungan keamanan regional Singapura sempat memburuk secara signifikan sejak resesi ekonomi pada tahun 1997-1998 tetapi ada beberapa tanda bahwa fungsi strategis negara kota ini akan meningkat secara signifikan di masa mendatang.
Dalam keadaan tidak pasti, para pemimpin Singapura -- sementara itu tidak pernah menunjuk pada suatu ancaman tertentu -- telah berulang kali menekankan pentingnya melanjutkan instrumen militer untuk melindungi negaranya dari ancaman konvensional negara-negara lain. Pembentukan pertahanan Singapura terus dikembangkan dan mengintegrasikan konsep-konsep operasional untuk informasi dan teknologi komunikasi secara berkelanjutan dan digunakan untuk komando dan kontrol.
Sejak tahun 1990-an, perkembangan Sospol khususnya di Indonesia telah menimbulkan kekhawatiran keamanan untuk Singapura. Berlanjutnya ketidakstabilan sosial, ekonomi dan politik, adanya konflik separatis dan antar-komunal di sekitar wilayah perbatasan Indonesia, telah menimbulkan complex emergency di pintu depan Singapura yang menimbulkan gangguan hukum dan ketertiban, konflik komunal, pembajakan, penyanderaan, gerakan populasi tidak diatur, kelaparan, penyakit merajalela dan bencana lingkungan. Tantangan baru lainnya -- baik dari pemerintah atau kelompok non-pemerintah -- mencakup berbagai kombinasi pengeboman, penggunaan senjata pemusnah massal (kimia atau biologis) atau serangan informasi, yang ditujukan pada penduduk sipil Singapura dan sasaran serangan pada infrastruktur nasional maupun militer.
Meskipun melawan ancaman asimetris akan menjadi tanggung jawab “Tim Depan”, sebuah lembaga non-militer di bawah Departemen Dalam Negeri (terutama polisi dan pasukan pertahanan sipil), Angkatan Bersenjata Singapura juga memiliki berbagai kemampuan yang relevan dengan kontinjensi tersebut (misalnya, operasi khusus militer dalam peran anti-teroris). Serangan 11 September 2001 memberi dampak pada keamanan Singapura. Pada bulan November 2001, Singapura mengumumkan akan menerapkan “keamanan tanah air” yang strategis dengan melibatkan kerjasama antara Kementerian Pertahanan, Departemen Pekerjaan Umum, Angkatan Bersenjata dan Polisi.
Pada awal dekade ini, pertahanan Singapura mulai mempertimbangkan isu yang lebih luas terkait dengan modernisasi Angkatan Bersenjata Singapura, dan partisipasi dalam RMA sebagai salah satu komponen dari proses transformasi militer secara keseluruhan. Pejabat senior Kementerian Pertahanan Singapura dan perwira kunci Angkatan Bersenjata Singapura melihat bahwa adanya keharusan untuk bertransformasi,
97
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 97 7/10/12 2:12 PM

di mana Angkatan Bersenjata Singapura harus mengembangkan fleksibilitas operasional dalam “landscape keamanan yang tidak menentu dan kompleks”, kemudian membuat sebagian besar anggaran pertahanan, kompensasi untuk pergeseran demografis yang akan mengurangi kekuatan personel, dan mengeksploitasi RMA semaksimal mungkin.
Dalam edisi terbaru Pointer, Andrew Tan, mantan Direktur Kebijakan di Kementerian Pertahanan Singapura, mengkaji implikasi dari transformasi untuk Angkatan Bersenjata Singapura tersebut. Ia berpendapat bahwa perubahan dalam Angkatan Bersenjata Singapura akan melibatkan serangkaian adaptasi dengan lingkungan keamanan yang selalu berubah. Dengan kata lain, lebih dari sebuah evolusi dari transformasi revolusioner. Sementara mempertahankan kapasitasnya untuk mencegah serangan konvensional, Angkatan Bersenjata Singapura perlu menjauh dari kompetensi inti yang didasarkan pada setiap bentuk “keuntungan numerik” menuju pengembangan “kemampuan portofolio”, di mana ia tetap mempertahankan keunggulan kualitatif yang akan memberikan kepemimpinan politik Singapura berbagai pilihan dalam menghadapi beragam ancaman.
Dalam waktu dekat, pemikiran radikal tentang struktur Angkatan Bersenjata Singapura, peralatan, dan pelatihan, akan dikombinasikan dengan efek perkalian kekuatan sistem baru C4I. Ini menyiratkan bahwa Angkatan Bersenjata Singapura dapat berkembang secara substansial. Tentu saja, akan ada kontinuitas yang cukup besar dalam beberapa bidang kebijakan pertahanan, misalnya wajib militer dan cadangan tenaga kerja Angkatan Bersenjata Singapura itu. Pada saat yang sama, ada kemungkinan akan kerjasama yang lebih erat antara Kementerian Pertahanan Singapura dan Angkatan Bersenjata Singapura di satu sisi, dan non militer di badan keamanan pada sisi lainnya.
Konteks transformasi adalah kemampuan beradaptasi dengan RMA untuk kepentingan nasional Singapura. Meskipun dampak dari transformasi untuk membuktikan sifat evolusioner daripada revolusioner, dampaknya dalam jangka menengah-jangka panjang mungkin masih lama, karena transformasi harus disesuaikan dengan kemampuan militer dan kemungkinan adanya kendala anggaran dan demografis.
IndiaSikap militer global dalam melakukan RMA telah dipengaruhi oleh operasi militer AS di Afghanistan dan Operasi Kebebasan di Irak yang menunjukan keunggulan teknologinya. Yang menakjubkan adalah militer AS mampu menguasai medan pertempuran walaupun jarak operasi yang sangat jauh dan dengan jumlah pasukan
98
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 98 7/10/12 2:12 PM

yang relatif sedikit. Operasi militer AS di Irak juga sekali lagi memberikan wawasan baru bagaimana pasukan yang relatif sedikit yang didukung teknologi modern mampu menaklukan musuh dengan cepat. Namun ada juga sebagian kalangan yang mengatakan bahwa operasi di Afghanistan dan Irak tidak mendatangkan perdamaian. Meskipun hal tersebut setidaknya benar, namun dua perang tersebut telah memacu kepemimpinan militer di seluruh dunia untuk meninjau kembali doktrin, organisasi, kekuatan struktur terkait dengan metode menggunakan teknologi terbaru. Mengadopsi teknologi baru memang sangat perlu dalam menghadapi perang. 32
Konflik dan kekerasan yang mempengaruhi keamanan dan stabilitas India juga berdampak pada militer India, seperti konflik konvensional, kekerasan etnis dan sektarian, narkotika, imigran gelap, fundamentalis agama, dan teroris. India menghadapi tantangan internal yang sangat serius, tata kelola yang buruk, administrasi yang buruk, hukum yang tidak memadai dan korupsi yang merajalela. Militer diperlukan untuk membantu pemerintahan sipil untuk menstabilkan situasi tersebut. Pada dasarnya militer India menghadapi tantangan besar karena adanya kebutuhan untuk mempelajari konsep-konsep transformasi dengan seksama.
Transformasi militer India akan melibatkan perubahan dari industri militer yang sudah tua menjadi yang terkini dan dilengkapi serta dilatih untuk melakukan operasi konvensional, menyerang dan bertahan di era informasi ini sehingga mampu memerangi terorisme yang disponsori oleh negara atau aktor non negara, dan juga menangkal serangan cyber, perang biokimia dan manipulasi media. Jadi kemampuan perang dari angkatan bersenjata harus melayani bentuk hibrida dari perang, karena itu organisasi angkatan bersenjata harus menjadi lebih fleksibel untuk dapat menyesuaikan diri dengan berbagai situasi.
RMA sekarang dikatakan sebagai “saat strategis”, sementara banyak pihak mengatakan bahwa perang masih harus dilakukan dengan cara yang berbeda. India juga berkeinginan untuk melakukan RMA, tapi harus didukung oleh lembaga dan agen untuk implementasinya. Instrumen militer Network Centric Warfare (NCW) harus ditempa dengan organisasi gabungan atau terpadu, teknologi baru, jaringan komunikasi, pembuatan senjata, perubahan sikap pemimpin dalam mengakomodasi RMA baru dan secara substansial meningkatkan ketrampilan seluruh jajaran. Angkatan Bersenjata India masih merencanakan secara eksklusif (perencanaan pelayanan tunggal) dan bercita-
32 V.K. Kapoor .RMA and India’s Military Transformation. Journal of Defence Studies Vol. 2 No. 2 2008. Artikel ini diunduh dari: http://www.idsa.in/jds/2 2 2008 RMAandIndiaMilitaryTransformation VKKapoor.
99
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 99 7/10/12 2:12 PM

cita memiliki dan mengadopsi sistem teknologi tinggi dari Rusia, Perancis, AS, Israel atau Inggris dengan model “berdiri-sendiri” dalam setiap layanan tapi bersinergis.
Teknologi Angkatan bersenjata India kini menghadapi era teknologi yang sama sekali baru, yang dihasilkan melalui kemajuan di bidang teknologi miniaturisasi, digitalisasi, ilmu pengetahuan terkini, bioteknologi, teknologi sensor, teknologi siluman, komunikasi dan teknologi informasi. India perlu mengintegrasikan semua teknologi baru tersebut sebagai sistem warfighting yang kebutuhannya adalah untuk berevolusi menjadi warfighting ajaran baru.
Beberapa langkah India untuk mencapai transformasi militer:1. Preparation. Menyiratkan bahwa RMA terjadi setelah periode panjang reformasi
dan mutlak perlu persiapan panjang.2. Recognition of Challenge. Menjelaskan bahwa RMA dibutuhkan karena dinilai
penting. Dan merupakan manifestasi dari reorientasi-radikal dari sikap politik/reorientasi politik yang radikal terhadap konflik Kargil33 dan Operasi Parakram.34
3. Parentage. Agar RMA menjadi sukses, maka dibutuhkan pengaruh politik atau patronase politik. Misalnya, RMA tahun 1990 di AS, dimotori oleh Andrew Marshall sebagai orangtua dan pelindung intelektual yang mendapatkan dukungan dari Menteri Pertahanan William J. Perry dan Wakil Kepala Staf gabungan, William A. Owens.
4. Enabling Spark. Menyiratkan bahwa RMA seperti NCW harus dibangun dengan upaya revolusioner.
5. Strategic Moment. RMA berisi moment strategis, mendorong terciptanya strategi baru dan menantang.
6. Institutional Agency. RMA memiliki lembaga dan agen untuk implementasi, organisasi militer sesuai dengan budaya militer, doktrin dan operasional yang inovatif, dan konsepnya diperoleh melalui “seni operasional” dan pelatihan yang intensif.
7. Instrument. Harus dipahami oleh militer dan harus sesuai dengan ukuran serta dalam konteks India.
33 Konflik Kargil adalah konflik bersenjata antara India dan Pakistan yang terjadi antara Mei dan Juli 1999 di distrik Kargil, Kashmir. Penyebabnya adalah masuknya pasukan Pakistan dan militan Kashmir ke wilayah India pada Line of Control, yang merupakan perbatasan de facto antara kedua negara. 34 Operasi Parakram adalah operasi militer India sebagai reaksi serangan teroris di Parlemen pada tanggal 13 Desember 2001. Operasi dengan mobilisasi skala penuh pertama sejak Perang India-Pakistan 1971 ini dimulai pada tanggal 15 Desember 2001 dan berakhir pada tanggal 16 Oktober 2002.
100
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 100 7/10/12 2:12 PM

8. Execution and Evolving Maturity. Memperjelas tentang pentingnya strategi, adanya tes dan percobaan serta konsekuensi dari penggunaan RMA. Langkah ini pada dasarnya mengacu kepada militer dan strategi efektif yang akan dicapai dengan menerapkan RMA.
9. Feedback and Adjustment. Harus memiliki potensi untuk memicu pembaharuan RMA.Sembilan langkah tersebut hanya sebagai alat analisis dan tools untuk memahami
proses RMA. Perubahan dan transformasi dalam Angkatan Bersenjata India membutuhkan sikap mendasar dari kaum militer untuk menerima perubahan, juga mendidik kepemimpinan politik sehingga proses transformasi menjadi kebutuhan militer bersama dengan para stakeholder. Sifat perang di masa depan akan memaksa kita untuk berpikir lebih besar, bermanuver lebih lincah, lebih cepat tanggap dan pasukan yang lebih tangkas. Para kepala staf pertahanan agar mengkoordinasi dan mendorong proses transformasi ke tingkatan tertinggi sehingga menjadi sebuah kebutuhan.
4.4.
Perbandingan Kasus Transformasi Militer Cina dan Amerika Serikat
Mengapa Cina dan AS perlu dibandingkan satu dengan yang lainnya dalam melihat proses transformasi yang pernah dan sedang berlangsung dalam institusi militer mereka. Hal ini tidak lain karena perkembangan dinamika ekonomi politik global yang sepertinya mengarah pada pengerucutan kekuatan dunia menjadi dua kutub kekuatan. Meskipun di satu kutub, AS pada saat ini terlihat terlalu lemah untuk dikatakan memiliki kekuatan super power akibat krisis ekonomi yang melanda mereka, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kekuatan AS masih dilihat sebagai satu-satunya kekuatan ekonomi politik dunia yang bisa mendorong proses-proses perubahan di luar AS itu sendiri. Sementara itu Cina, yang saat ini bisa dikatakan sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk paling besar, industri militer dan teknologi informasi yang cukup maju serta pertumbuhan ekonomi paling baik sedunia perlahan tapi pasti mulai menapaki diri sebagai salah satu negara adidaya di dunia.
Kendati begitu, potensi konflik dan ketegangan yang ada saat ini, baik antara AS dan Cina maupun antara Cina dengan negara-negara lain dan AS dengan negara-negara lain wajib diwaspadai karena dinamika politik global yang terus bergerak dan jika merujuk pada apa yang dikatakan oleh Giddens, risiko dari konflik dan ketegangan
101
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 101 7/10/12 2:12 PM

itu tentu saja tidak terbatas pada negara atau wilayah yang berkonflik, namun juga
bisa bersifat massif dan mencapai relung-relung terdalam dari wilayah satu negara.
Dengan pandangan seperti ini, kiranya secara sosiologis kita perlu melihat sejauh mana
kesiapsiagaan dari militer kedua negara dalam menghadapi potensi konflik yang “bakal”
terjadi. Dalam pada itu, proses transformasi yang dialami oleh militer kedua negara
menjadi penting untuk ditelaah dan dipelajari, bukan saja demi kepentingan strategis
melihat potensi dan risiko perang yang mungkin muncul, tetapi juga bisa digunakan
sebagai bahan bagi kita untuk belajar melakukan transformasi militer dari dua cara
yang relatif berbeda dengan struktur ekonomi politik yang berbeda pula. Diharapkan
dari proses transformasi yang telah dilakukan kedua negara tersebut, kita akan bisa
melihat keputusan-keputusan penting apa yang harus kita perhatikan ketika Indonesia
memutuskan untuk melakukan transformasi institusi militernya dalam menghadapi
ancaman dan tantangan global.
CinaKarakteristik paling menarik dalam melihat persoalan militer Cina adalah relasi
antara institusi militer mereka, People Liberation Army (PLA) dengan Partai Komunis
Cina (China Comunist Party). Dalam pidato ulang tahun ke-80 PLA tahun 2007,
Presiden Hu Jintao yang merangkap sebagai Sekjen Partai Komunis Cina (PKC) dan
salah seorang pemimpin utama di tubuh militer Cina menyatakan dengan tegas bahwa
akan selamanya militer Cina berada di bawah komando PKC. 35
Meskipun terkesan sangat Barat centris, Richard D. Fisher (2008), dalam salah satu
bukunya yang menjelaskan mengenai proses modernisasi militer Cina menceritakan
banyak hal mengenai bagaimana Cina sebagai salah satu kekuatan ekonomi politik
dunia menempatkan kekuatan militer sebagai satu perangkat yang tidak saja ditujukan
bagi upaya mengatasi ancaman pertahanan dan keamanan nasionalnya, melainkan
juga secara brilian mengintegrasikannya dengan sektor-sektor lain sehingga secara
singkat bisa dikatakan bahwa transformasi militer Cina adalah adalah salah satu wujud
transformasi nasional Cina. Dengan sangat meyakinkan, transformasi militer Cina
diletakkan sebagai dasar untuk juga mengembangkan industri militer dan industri
teknologi komunikasi mereka yang pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan
perekonomian Cina. Meskipun dalam beberapa hal, produksi industri militer Cina
memiliki banyak kelemahan, namun hal itu tidak bisa menghalangi perkembangan
ekonomi mereka yang salah satunya diakibatkan oleh semakin majunya Cina dalam
35 Richard D. Fisher, China’s Military Modernization:, (Greenword Publishing Group, 2008) hal. 15.
102
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 102 7/11/12 11:34 AM

memproduksi senjata-senjata perang dan peralatan komunikasi serta teknologi informasi.
Sementara itu, Elinor Sloan (2008) menegaskan konteks strategis keamanan Cina yang mulai berubah menjadi pendorong utama dari proses transformasi militer mereka. Perubahan itu di antaranya menyangkut strategi pertahanan yang berbasis daratan. Jika sebelumnya (pasca Perang Dingin) Cina masih menempatkan persoalan pertahanannya berbasiskan daratan (landbase) karena ancaman paling nyata dari keamanan nasional mereka adalah mengenai wilayah perbatasan yang bersebelahan dengan 14 negara, terutama yang berbatasan dengan Uni Sovyet, saat ini hal tersebut telah berubah. Semakin mesranya hubungan Cina dengan Rusia dan beberapa negara di kawasan Asia Tengah melalui Organisasi Kerjasama Shanghai (Shanghai Cooperation Organization) mendorong Cina melakukan transformasi militernya terutama yang terkait dengan permasalahan pertahanan laut. Cina berkeinginan memindahkan kekuatan landas kontinen mereka menjadi kekuatan laut. Kendati transformasi itu didorong oleh satu konteks strategis yang lebih baru, persoalan klasik masih tetap menjadi perhatian mereka, terutama terkait hubungan Cina dengan Taiwan, serta persoalan sumber daya alam di Laut Cina Selatan yang melibatkan sengketa dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara.
Kebijakan transformasi militer yang juga sekaligus ditempatkan sebagai kebijakan tranformasi nasional, sekali lagi tidak terlepas dari keberadaan militer Cina yang secara langsung menjadi sub organisasi dari PKC, sehingga beragam kebijakan partai mendapat dukungan yang sangat kuat dari institusi militernya. Secara jelas dalam laman web xinhuanet mengenai Pertahanan Nasional Cina, negara ini merencanakan proses transformasi militernya berdasarkan tantangan kekinian dari persoalan keamanan nasionalnya, di antaranya: persoalan dinamika krisis ekonomi global yang secara langsung menuntut adanya tanggung jawab global dalam rangka menjaga stabilitas keamanan internasional dan semakin kuatnya peranan Asia dalam kancah ekonomi politik global sehingga menjalin komunikasi yang intensif dengan negara-negara di Asia menjadi satu kepentingan yang tidak bisa dikesampingkan. Selain itu dalam laman web itu juga dijelaskan bagaimana Cina memandang ancaman-ancaman terhadap integritas nasional mereka seperti, persoalan Semenanjung Korea, persoalan kemerdekaan Taiwan, Tibet serta persoalan Laut Cina Selatan. 36
Kendati Cina mampu mendefinisikan secara jelas persoalan-persoalan yang
36 Sumber Keterangan ini diunduh melalui: http://news.xinhuanet.com/english2010/Cina/2011-03/31/c_13806851
103
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 103 7/10/12 2:12 PM

menyangkut ancaman dan tantangan terhadap keamanan nasionalnya, tetapi secara tegas mereka juga menyatakan diri bahwa kebijakan keamanan nasional mereka dilandasi oleh semangat perdamaian, seperti yang mereka nyatakan dalam Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai (Five Principal of Peaceful Coexistence). Kelimanya itu antara lain: Cina akan memegang teguh nilai tradisi dan kepercayaan mereka yang menyatakan bahwa perdamaian adalah di atas segalanya, menyelesaikan berbagai persoalan dan perselisihan dengan cara-cara damai, cermat dan hati-hati terhadap isu peperangan, strategi menyerang setelah diserang lebih dahulu dan Cina tidak akan menghegemoni, apakah itu dengan pendekatan ekspansi militer baik sekarang maupun di masa depan dalam kondisi ekonomi apapun.37
Namun demikian, Fisher (2008) yang selama beberapa kurun waktu telah menjadi pengamat perkembangan militer Cina, mengkhawatirkan slogan yang sering dikumandangkan oleh Cina bahwa mereka hanya akan menyerang setelah diserang lebih dahulu, terlebih dalam menggunakan senjata nuklir. Menurut Fisher, pemaknaan dari diserang lebih dahulu ini bisa berarti sangat luas. Dalam pandangannya, makna penyerangan bisa saja diartikan oleh Cina sebagai bentuk intervensi atas satu kebijakan mereka di satu negara atau di negara Cina sendiri. Di sinilah letak bias dari kebijakan Cina menurut Fisher. Ia menganggap bahwa Cina memiliki potensi untuk melakukan invasi ataupun serangan militer ke wilayah-wilayah yang selama ini telah menjadi semacam area sengketa tradisional Cina secara turun temurun, sebut saja semacam Taiwan, Semenanjung Korea, Tibet ataupun Laut Cina Selatan. Meskipun kekhawatiran ini lebih terasa sebagai kekhawatiran Barat terhadap semakin naiknya Cina sebagai salah satu kompetitor AS, namun segala kemungkinan bisa terjadi ketika persoalan kepentingan nasional terganggu.
Dalam rencana strategis pertahanan Cina tahun 2006, juga di laman web yang sama, secara eksplisit militer Cina menyatakan bahwa pada tahun 2010 akan diselesaikan tahap pertama, yakni landasan dari proses transformasi militer Cina, kemudian tahap kedua terkait progres atau kemajuan secara umum militer Cina akan diselesaikan pada tahun 2020, dan setelah itu memasuki tahap ketiga yang secara mendasar akan diwujudkan sebuah kekuatan militer Cina yang menguasai kemampuan informasi dan mampu memenangi peperangan informasi pada pertengahan abad 21. 38
37 Dituangkan dalam cetak biru pertahanan nasional Cina tahun 2010.38 Richard D. Fisher. op.cit. hal. 66.
104
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 104 7/10/12 2:12 PM

Masih menurut Fisher, ada dua fase mendasar dari proses modernisasi militer Cina. Fase pertama dimulai sejak Deng Xiaoping menjadi Wakil Perdana Menteri Cina. Fase ini bisa dilihat sebagai fase mengejar ketinggalan (catch-up) dengan membangun cadangan militer regional yang besar seperti halnya Korea dan Taiwan. Fase kedua adalah periode pengembangan dalam rangka menyelesaikan target-target pada fase pertama, sekaligus mencoba mempersiapkan diri dalam rangka menghadapi persoalan global. Era 90-an adalah era uji coba mereka. Kendati begitu, banyak pelajaran penting yang berhasil mereka peroleh dalam rangka transformasi militer Cina. Ada tiga area transformasi yang pada gilirannya menjadi pokok perubahan dalam militer Cina, yaitu: doktrin, industri militer dan revolusi dalam bidang informasi. Untuk itu, ada dua faktor pendorong yang mereka siapkan untuk mensukseskan reformasi tiga area yang telah disebutkan sebelumnya. Pertama adalah efisiensi dari personel militer39 dalam rangka perubahan doktrin40 dari People”s War menjadi serdadu-intensif, dan kedua adalah perkembangan yang cukup cepat pada industri teknologi komunikasi, informasi, internet serta infrastruktur broadband.41
Dalam hal organisasi, transformasi yang bisa diidentifikasi oleh Fisher antara lain, keberadaan tujuh Wilayah Militer (Military Regions) yang menjadi kekuatan mendasar dari militer Cina telah diintegrasikan dengan pengembangan wilayah lokal. Hal ini menyangkut penyediaan logistik militer mereka yang dalam rangka pengembangan ekonomi lokal diberikan kesempatan kepada kontrantor-kontraktor lokal agar ekonomi sekitar bisa tumbuh dan hal ini juga mengakibatkan efisiensi pengelolaan logistik militer mereka. Dari sisi personel, militer Cina saat ini telah memiliki personel yang bukan berasal dari milliter dalam jumlah cukup banyak karena adanya tuntutan untuk mengoperasikan senjata-senjata militer teknologi tinggi. Selain itu telah dibentuk Korps Bintara (Non Commisioned Officers Corps) yang secara khusus menangani persenjataan canggih yang mereka miliki. Cina juga menempatkan pendidikan militer profesional sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas prajuritnya dengan cara membuka peluang lebih besar bagi para perwiranya untuk memperoleh pendidikan lanjut. Selain itu, pelatihan tempur juga menempati posisi penting dalam rangka meningkatkan kapasitas organisasi dan sumber daya manusia militer Cina.42
39 Sejak 1985-2005 Cina telah mengurangi jumlah personel militer mereka sebanyak 1,7 juta orang, termasuk di dalamnya 170.000 perwira.40 Di dalam PLA tidak dikenal istilah doktrin, yang ada adalah teori operasional dan praktik operasional.41 Richard D. Fisher. op.cit. hal. 67.42 Ibid. hal. 73.
105
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 105 7/10/12 2:12 PM

Dari penjelasan singkat di atas, kiranya kita bisa melihat bagaimana transformasi militer Cina adalah bagian kecil dari tranformasi nasional negara mereka. Meskipun secara struktural militer Cina berada di bawah PKC, tetapi proses transformasi tetap bisa dilakukan sesuai dengan rencana yang mereka susun. Di Cina, seperti kita ketahui, politik adalah panglima dari setiap keputusan yang dikeluarkan oleh negara. Dengan menempatkan transformasi militer sebagai bagian dari transformasi nasional mereka, Cina berhasil mengintegrasikan hasrat modernisasi militer Cina dengan perkembangan industri dan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. Selain itu, meskipun terkesan mengadopsi strategi reformasi militer Barat dan AS, efisiensi prajurit dan tuntutan modernisasi Alutsista Cina menunjukkan bahwa nilai-nilai yang berasal dari gagasan RMA juga diyakini kebenarannya oleh mereka. Hanya saja, menempatkan RMA sebagai salah satu cara dalam mencapai postur militer yang kuat dan ideal, tidak ditunjukkan oleh Cina dengan bergantung dengan industri militer negara maju, melainkan dimanfaatkan oleh mereka untuk menumbuhkan inisiatif pengembangan industri nasionalnya.
Amerika SerikatPasca Perang Dingin, komunitas pertahanan di AS menyadari pentingnya satu proses perubahan dan transformasi militer melihat kenyataan bahwa mereka saat itu menjadi satu-satunya negara dengan kemampuan pengembangan industri militer tanpa kompetitor. Oleh karena itu, mereka mendesak agar pemerintah AS sesegera mungkin melakukan investasi teknologi militer terbarukan dan konsep inovasi perang yang dirancang untuk menghadapi ancaman masa depan meskipun belum ada musuh yang teridentifikasi secara jelas (Butler: 2010). Dalam Joint Vision 2010 yang diterbitkan pada tahun 1997, kemudian direvisi kembali pada tahun 2000 dengan Joint Vision 2020, ditegaskan perihal pengembangan militer AS dalam rangka menghadapi siapa saja, baik negara, kelompok maupun perorangan yang akan merongrong kepentingan dan nilai-nilai AS dan sekutunya. 43
Kemenangan AS pada Perang Dingin tak pelak mendorongnya menjadi satu-satunya kekuatan dunia yang paling disegani. Kemenangan ini pula yang oleh beberapa kalangan dianggap menjadi salah satu tonggak dari transformasi militer AS yang secara umum sering diasosiasikan dengan gagasan mengenai RMA (lihat: Blaker (2007); Sloan (2008); Adamsky (2010)). Meskipun RMA dan transformasi militer sama-sama menekankan pentingnya perubahan dalam institusi militer AS, dalam Quadrennial
43 Lihat R. Butler,”The US Shift Beyond Capital Asset” dalam Scott Jasper (ed). Transforming Defense Capabilities: New Approaches for International Security (Vivabooks, 2010).
106
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 106 7/10/12 2:12 PM

Defence Review (QDR) 2001 yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan AS, dikatakan secara tegas bahwa antara RMA dan transformasi militer adalah dua hal yang berbeda. RMA menekankan pada satu titik tujuan atau capaian yang dikehendaki dari sebuah proses perubahan yakni kata revolusi itu sendiri. Sementara transformasi lebih menekankan pada satu proses perubahan yang berjalan terus-menerus dalam rangka merespon dinamika sosial, ekonomi dan politik dunia yang senantiasa berubah.44 Sesungguhnya tidak ada perbedaan yang mendasar dari RMA dan transformasi militer itu sendiri seperti yang ditegaskan oleh Sloan bahwa transformasi militer bisa saja dikatakan sebagai langkah lanjutan dari RMA. Jika konteks strategis dari RMA itu adalah pasca Perang Dingin ketika AS terlibat dalam Perang Teluk Pertama, maka transformasi militer yang dimaksud di sini lebih kepada respon AS atas berubahnya lingkungan strategis pasca penyerangan Pentagon dan WTC 11 September 2001. Jika sebelumnya konsentrasi AS adalah pada negara yang secara nyata menyerang dan merongrong kepentingan nasional AS, maka pasca 11 September 2001, AS lebih fokus pada upaya pertahanan dan pencegahan dari serangan terorisme. Dalam konteks ini, kategori musuh menjadi lebih luas, bisa perorangan, kelompok maupun negara yang melindungi ataupun bekerjasama dengan jaringan terorisme global. Selain itu, penekanan mengenai nilai-nilai universal yang diakui sebagai nilai yang bersumber dari prinsip-prinsip moral bangsa AS juga menjadi salah satu alasan mengapa prinsip-prinsip peperangan AS mengalami perubahan mendasar. Persoalan HAM dan demokratisasi bisa menjadi dalih bagi AS untuk melakukan tekanan pada negara-negara yang tidak menjadikan nilai tersebut sebagai acuan dalam menjalankan sistem ketatanegaraannya. Meskipun dalam prinsip kedaulatan nasional suatu negara hal ini adalah wewenang penuh negara tersebut, namun dengan posisi AS sebagai polisi dunia sangat dimungkinkan terjadi.
Pada beberapa literatur yang menjelaskan perihal transformasi militer di AS, keberadaan Sekertaris Pertahanan Donald Rumsfield seringkali disebut sebagai tokoh yang berada di balik proses transformasi tersebut. Sebagai orang paling muda sekaligus orang paling tua yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Pertahanan AS, pemikiran Rumsfield diakui cukup banyak mendominasi pemikiran strategis AS dalam memandang keamanan nasional mereka dan model RMA yang mereka lakukan.45
44 Elinor Sloan. “Military Transformation and Modern Warfare : A Reference Handbook”. (Prageger Security International, 2008) hal. 845 Donald Rumsfield pernah ditunjuk sebagai Sekertaris Pertahanan AS pada masa presiden Ford pada pertengahan tahun 1970-an, dan kemudian diangkat lagi dalam posisi dan jabatan yang sama oleh Presiden Bush pada tahun 2000.
107
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 107 7/10/12 2:12 PM

Selain itu, nama lain yang juga kerap muncul terkait bagaimana transformasi militer
itu dilakukan adalah Laksamana Arthur Cebrowski (lihat: Blaker (2007) dan Butler
(2010)).
Elinor Sloan, seorang Associate Professor bidang Hubungan Internasional yang
mengajar di Carleton University, Ottawa, Kanada, menjadi penasehat militer pada
Departemen Pertahanan Kanada dan pernah menjadi tentara sampai pangkat Kapten
pada Angkatan Udara Kanada, menjelaskan perihal transformasi militer yang terjadi
di banyak negara, khususnya AS. Pergeseran pemahaman dari RMA ke transformasi
militer tidak lantas mengakibatkan adanya penyesuaian dalam hal organisasi, doktrin
dan teknologi militer pada Angkatan Bersenjata AS. Masih menurut Sloan, kendati
terjadi pergeseran, namun banyak para sarjana yang tetap mengidentikkan transformasi
militer sebagai langkah lanjut dari RMA, karena selain teknologi, doktrin dan
organisasi yang ada mirip seperti masa RMA, hanya kapasitas dan kapabilitasnya saja
yang ditingkatkan. Rumsfield dalam Sloan (2008) menegaskan bahwa transformasi
militer AS adalah pengembangan secara cepat penyebaran pasukan, integrasi kekuatan
gabungan secara penuh, kemampuan menciptakan dampak kerusakan yang besar di pihak
musuh secara cepat dengan kekuatan laut dan udara, yang kesemuanya itu mencakup
cara pikir dan cara perang baru. Sejalan dengan hal itu, dalam pengakuannya, Arthur
Cebrowski yang mengepalai Kantor Transfromasi Angkatan Bersenjata AS menekankan
pentingnya prinsip moral dalam setiap prajurit militer karena pada dasarnya penciptaan
teknologi militer untuk keperluan perang adalah sebagai kebutuhan dari upaya manusia
dalam menegakkan prinsip moral yang mereka junjung tinggi. Oleh karena itu, masih
menurut Cebrowski, personil militer mesti mengetahui keterkaitan antara penggunaan
kekuatan militer dan kekerasan dalam jumlah yang besar dengan prinsip-prinsip moral
yang mereka perjuangkan. 46
Dari sisi teknologi transformasi militer pasca 11 September 2001, sedikit banyak
masih mengadopsi apa yang digunakan dalam proses RMA, di antaranya Presision-Guided Munition (PGMs), Intelligence, Surveillance and Reconnaisance (ISR),
Capabilities, Control, Communication, Computing and Intelligence prosessing (C4I).
Kemudian penggabungan dari ISR dengan C4I menjadi C4ISR. Sementara itu, terkait
doktrin militer mereka, ada beberapa perubahan yang sebenarnya lebih bisa dikatakan
pengembangan dari doktrin pada masa RMA, di antaranya: Standoff Precision Force,
Unamanned Combat Vehicle (termasuk di dalamnya kendaraan militer tanpa awak),
46 James R. Blaker, ibid. hal 2
108
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 108 7/11/12 11:34 AM

Expeditionary and Highly Mobile Forces (salah satunya kemampuan militer di kapal induk yang berlayar terus menerus dan mobil pengangkut pasukan skala kecil), Littoral Warfare (menciptakan pangkalan armada perang di tengah lautan yang melibatkan berbagai kapal besar dengan fungsi yang beragam), Jointness (operasi gabungan kesemua matra angkatan perang AS). Transformasi militer AS juga mendorong semakin berkembangnya organisasi pasukan khusus, operasi anti pemberontakan, serta tugas-tugas rekonstruksi dan stabilisasi kawasan.
Dalam konteks transformasi yang mereka lakukan, Sloan mengidenfikasi dua komponen transformasi itu, di antaranya: pertama, mencari kombinasi yang tepat dari kapabilitas militer dalam rangka merespon baik perang konvensional maupun non konvensional, kedua, mempersiapkan prajurit yang memiliki ketrampilan dan kualitas moral yang fleksibel dalam rangka menghadapi dua jenis peperangan tersebut. Oleh karenanya, pelatihan sumber daya manusia dalam tubuh institusi militer menjadi penting untuk dilakukan agar tujuan-tujuan yang telah direncanakan bisa dicapai secara efektif.
Yang terakhir, bukan berarti kurang penting dalam perbincangan transformasi militer AS adalah keterlibatan atau lebih tepatnya pelibatan sejumlah negara-negara yang menjadi sekutu AS untuk juga menggulirkan proses transformasi militer di negara mereka masing-masing. Beberapa negara yang terlibat itu di antaranya Inggris, Perancis, Jerman, Australia dan Kanada.
Berangkat dari penjelasan di atas, kiranya kita bisa melihat satu gambaran umum bagaimana transformasi militer AS berangkat dari pemahaman mereka terhadap lingkungan strategis yang terus menerus berubah. Pergeseran pemaknaan dari RMA ke transformasi militer menunjukkan adanya satu kesadaran para pemimpin militer dan pertahanan AS bahwa dinamika politik global termasuk globalisasi itu sendiri mengakibatkan perkembangan situasi yang kadang tidak terduga atau tidak terprediksi, oleh karenanya transformasi sebagai sebuah proses menjadi penting ketimbang hal itu dirumuskan sebagai tujuan. Transformasi militer AS tentu saja melibatkan investasi yang sangat besar pada industri pertahanan AS, baik industri persenjataan, teknologi informasi maupun industri keamanan swasta (private security institution). Keberadaan industri pertahanan ini tidak saja berfungsi untuk mendukung proses transformasi yang dijalankan oleh militer AS, melainkan juga oleh negara-negara yang menjadi sekutu AS seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahkan secara lebih luas, industri persenjataan itu juga mendukung proses transformasi militer negara berkembang, seperti Indonesia.
109
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 109 7/10/12 2:12 PM

110
Tabel 6. Pemetaan Pengalaman Transformasi Militer Negara-negara di Dunia
Diolah dari berbagai sumber
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 110 7/13/12 12:12 PM

111
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 111 7/10/12 2:12 PM

4.5.
Rangkuman
Tidak bisa dipungkiri bahwa tesis terbaik yang menjadi dasar dari proses transformasi militer suatu negara adalah dikarenakan ancaman dan tantangan keamanan nasional negara mereka. Kendati secara lebih spesifik, masing-masing negara memiliki definisinya sendiri-sendiri mengenai apa yang mereka maksud dengan keamanan nasional, karena terkait sangat erat dengan kepentingan nasional mereka. Ketika kepentingan nasional mereka dalam perjalanannya telah melampaui batas-batas ruang dan waktu, pada saat itulah biasanya, pendefinisian atas keamanan nasionalnya pun menjadi semakin luas, sehingga konsep-konsep keamanan nasional mulai melebar lebih jauh sampai menyentuh persoalan-persoalan yang pada mulanya merupakan persoalan sekunder, seperti kemanusiaan, lingkungan dan ekonomi. Pada titik inilah transformasi institusi militer di banyak negara menemukan pijakan yang lebih beragam sehingga arah perkembangannya juga dapat mengikuti dinamika pendefinisian keamanan nasional masing-masing negara.
Pada bagian ini kita bisa lihat bagaimana pola relasi yang terbangun di antara negara-negara di dunia terkait dengan urusan kemiliteran. Dari AS, pelajaran yang bisa kita peroleh adalah membangun institusi militer yang handal harus diiringi dengan industri militer yang memadai. Tetapi, perkembangan material itu tentu saja belum cukup karena hasrat dominatif sebagai negara adikuasa mensyaratkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh AS harus juga dilakukan oleh negara-negara lain. Sehingga konsep-konsep transformasi yang mereka kembangkan seperti gagasan RMA mesti ditularkan. Alhasil, ketika konsep-konsep tersebut diadopsi oleh negara lain, secara otomatis menciptakan ketergantungan teknologi persenjataan dan strategi perang. Pertama-tama tentu saja dialami oleh sekutu AS seperti negara-negara Eropa non Rusia, dan sebagian besar negara-negara di Asia, seperti Jepang dan Singapura. Kondisi ini secara resiprokal mendorong penguatan industri militer AS serta penelitian-penelitian terkait persenjataan perang.
Sementara itu, dari perkembangan militer Rusia, kita bisa melihat bahwa, pasca Perang Dingin tidak saja industri persenjataan mereka hancur, lebih dari itu, Rusia yang sebelumnya Uni Sovyet mesti menghadapi gejolak politik dalam negeri yang menyita banyak energi. Kelemahan ini menjadi pintu masuk yang sangat efektif bagi
112
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 112 7/10/12 2:12 PM

AS dan sekutunya untuk juga memasukkan prinsip-prinsip baru dalam dunia militer dan peperangan sehingga dalam banyak segi, Rusia seperti mengikuti kehendak AS dan sekutunya. Ketimbang menghadapi ancaman embargo ekonomi yang bisa lebih menghancurkan tatanan politik dalam negeri, mau tidak mau Rusia berkompromi dengan kondisi luar negeri. Inilah yang membedakan Rusia dengan Cina. Dengan sistem politik kenegaraan yang sentralistik, Cina bisa unggul dalam hal stabilitas dalam negeri. Meskipun dianggap oleh dunia luar Cina tidak demokratis, hal ini tetap menjadi modal besar bagi mereka untuk membangun satu kekuatan militer yang tidak saja banyak dalam jumlah personel, tetapi mampu mengembangkan sistem persenjataan militer yang didukung oleh industri militer negara yang kuat. Terlepas dari banyak pihak yang menilai bahwa kualitas produk industri persenjataan Cina berada jauh di bawah rata-rata, tetapi sebagai sebuah proses, perkembangan ini cukup mengagetkan pihak AS dan Barat. Belajar dari apa yang telah terjadi pada AS ketika menjadi negara adidaya, ada kesan kuat Cina juga akan mencoba memperluas pengaruh ekonomi politiknya dengan menyebarluaskan produk industri persenjataan mereka ke berbagai negara di dunia melalui berbagai cara. Dalam konteks ini, secara sosiologis membuktikan tesis klasik yang mengatakan bahwa kapitalisme industri – terlepas dilakukan oleh swasta ataupun negara – akan terus menerus mencari jalan untuk memperluas jangkauan pemasaran produknya akibat kelebihan kapasitas.
Selain itu, negara-negara Asia yang termasuk negara berkembang, jika ditinjau dari segi persenjataan perang, saat ini masih berada pada posisi subordinat dari negara-negara yang memiliki industri persenjataan canggih. Ketimpangan ini tidak jauh berbeda dengan komoditas lain selain persenjataan militer. Dengan perkembangan industri persenjataan Cina yang cukup pesat sekarang ini, paling maksimal adalah bertambahnya alternatif persenjataan. Tetapi apakah itu akan berdampak pada proses transformasi militer di dalam tubuh angkatan bersenjatanya atau perkembangan industri militer dalam negeri, terlalu dini untuk mengatakan hal tersebut akan terjadi.
Dari penjelasan yang ada, tampak nyata bahwa kunci transformasi militer di beberapa negara adalah peranan otoritas politik. Kecuali di Cina, posisi militer berada di bawah otoritas sipil dengan beragam corak kepemerintahannya. Tetapi intinya adalah sejauh mana institusi militer itu akan bisa berkembang dan sekaligus responsif terhadap perkembangan-perkembangan yang terjadi di dunia, tidak bisa dilepaskan dari kemampuan otoritas negara dalam membaca peta situasi ataupun dinamika
113
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 113 7/10/12 2:12 PM

ekonomi politik global. Kendati begitu, pemaknaan militer berada di bawah otoritas sipil sesungguhnya secara sosiologis tidak bisa begitu saja diartikan sebagai sebuah keterpisahan dengan batas yang padat atau jelas. Keterpisahan antara otoritas negara dengan militer, dalam banyak kasus dan dalam contoh-contoh proses transformasi di negara-negara lain, menunjukkan bahwa militer sebagai institusi maupun anggota militer secara individual memiliki sumbangsih yang cukup besar dalam kerangka mendorong lahirnya satu kebijakan transformasi militer satu negara. Artinya, men-dikotomikan secara kaku antara militer dengan institusi sipil yang menguasai negara sudah barang tentu kurang efektif dalam konteks memandang lingkungan strategis termasuk potensi dan ancaman yang melingkupi keamanan nasional suatu negara. Oleh karena itu, menempatkan individu-individu militer dalam pemerintahan sipil dan sebaliknya kalangan sipil di militer sehingga institusi militer terbuka untuk menerima dan menginternalisasikan pemikiran-pemikiran dari kelompok masyarakat sipil menjadi pilihan yang paling logis jika kita menginginkan sebuah proses transformasi yang bisa meminimalisir inefisiensi maupun konflik. Selain itu upaya ini juga bisa sedikit demi sedikit menandingi wacana dikotomi sipil-militer yang terlanjur dimaknai secara serampangan oleh berbagai kelompok.
Belajar dari apa yang telah dilakukan oleh Cina dalam rangka menjalankan agenda transformasi militer nasionalnya, membangun industri persenjataan untuk kepentingan pertahanan nasional selain bisa mengurangi ketergantungan persenjataan impor dari negara maju, juga sekaligus bisa menjadi motor dari upaya transformasi nasional yang lebih luas, khususnya pada bidang ekonomi.
Bagi Indonesia, transformasi militer harus diletakkan dalam satu lingkup diskursus yang agak luas, transformasi militer harus dan mesti menjangkau aspek-aspek lain di luar institusi militernya, tentu bukan dalam rangka mengembalikan supremasi militer di dalam ranah sipil seperti di masa Orde Baru. Agenda ini mesti dilihat dalam cakrawala berpikir yang lebih kontekstual, bahwa persoalan pertahanan dan keamanan, bukan saja tugas dan tanggung jawab militer. Ketika perang sebagai pilihan terakhir telah diputuskan, tidak bisa tidak, tanggung jawab itu harus dijalankan oleh semua elemen di republik ini, pun bagi orang yang membenci perang itu sendiri. Oleh karenanya, transformasi militer Indonesia harus didukung oleh transformasi nasional masyarakatnya, sehingga masyarakat bisa semakin cerdas dan tidak senantiasa terjebak pada pola pikir lama warisan Orde Baru yang berhasil membangun momok militer itu sesuatu yang menakutkan dan tak kenal kompromi. Militer Indonesia harus menjadi militer baru dengan cakrawala berpikir dan bertindak yang baru pula.
114
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 114 7/10/12 2:12 PM

115
bab3-4 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 115 7/10/12 2:12 PM

116
bab5-6 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 116 7/10/12 2:16 PM

Bab V
Militer Indonesia dan Pemetaan Kebijakan• Reorganisasi dan Rasionalisasi Militer Indonesia dari Masa Ke Masa• Pengaruh Dinamika Lingkungan Global terhadap Militer Indonesia• Dampak Jangka Panjang Perkembangan Militer Indonesia• Rangkuman
117
bab5-6 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 117 7/10/12 2:16 PM

Bab V.
Militer Indonesia dan Pemetaan KebijakanPerkembangan militer Indonesia selama beberapa kurun waktu menunjukkan betapa sesungguhnya perubahan-perubahan terus terjadi, baik yang didorong oleh inisiatif-inisiatif yang muncul dari para pimpinan militer Indonesia yang visioner maupun yang dipengaruhi oleh dinamika lingkungan strategis yang terus berubah. Meskipun demikian, banyak pihak yang merasa bahwa lingkungan militer Indonesia sebagai institusi militer yang memiliki perbedaan karakteristik dengan institusi sosial lainnya cenderung resisten terhadap perubahan. Pada kenyataannya seperti yang akan dijelaskan dalam bab-bab setelah ini, perubahan yang tidak saja berada di dalam skala kualitatif melainkan juga kuantitatif, menunjukkan bagaimana dalam batas-batas tertentu perubahan pada tubuh militer Indonesia telah berlangsung sangat cepat. Faktor paling dominan yang kemudian mempercepat dinamika perubahan dalam tubuh militer Indonesia adalah disebabkan sistem komando dalam institusi militer yang cenderung meniadakan bentuk-bentuk kompromi pada setiap jenjang hierarki organisasinya. Padahal seperti kita ketahui, sebagai sebuah institusi yang secara legal diberikan otoritas dan wewenang untuk melakukan tindakan kekerasan, perubahan yang cepat dan radikal itu berisiko sangat tinggi. Apalagi mengingat dalam perkembangannya militer Indonesia tidak pernah lepas dari dinamika sosial, ekonomi dan politik yang melingkupi perkembangan Indonesia selama hampir tujuh dekade ini. Oleh karena itu, penulis akan berikan beberapa gambaran singkat tentang perkembangan militer Indonesia dari masa ke masa dan kemampuan adaptasinya terhadap berbagai persoalan yang timbul, baik yang bersumber dari persoalan internal maupun eksternal.
Untuk melihat sejauh mana kebijakan negara dalam pengembangan militer Indonesia dari semenjak berdiri sampai dengan hari ini, kiranya dibutuhkan semacam peta kebijakan yang memasukkan tahapan perkembangan militer Indonesia ataupun periodesasi sejarah yang tercatat menjadi momentum dari setiap perubahan yang dilakukan. Perlu disadari juga bahwa pembahasan mengenai perubahan kebijakan militer Indonesia amat sangat luas cakupannya. Oleh karenanya, dalam bagian ini hanya akan dilihat cakupan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengorganisasian militer Indonesia itu sendiri dan konteks strategis yang melatari terjadinya perubahan tersebut.
118
bab5-6 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 118 7/10/12 2:16 PM

5.1.
Reorganisasi dan Rasionalisasi Militer Indonesia dari Masa Ke Masa
Pembentukan Badan Keamanan RakyatSetelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia masih harus berjuang menegakkan kedaulatan negara dengan menghadapi ancaman kekuatan asing yang ingin kembali berkuasa di Indonesia, yaitu pihak Sekutu, dan Belanda. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam sidangnya yang pertama tanggal 18 Agustus 1945 hanya memilih Presiden dan Wakil Presiden serta mengesahkan UUD 1945. Pemerintah Republik Indonesia (RI) ketika itu tidak segera membentuk tentara. Pimpinan nasional berpendapat bahwa pembentukan sebuah tentara nasional pada saat itu dikhawatirkan akan memancing pukulan dari gabungan kekuatan Sekutu, dan Jepang yang ditugasi oleh Sekutu untuk menjaga status quo di daerah-daerah yang didudukinya termasuk Indonesia, padahal kekuatan nasional belum mampu menghadapinya. Tetapi serangan-serangan semakin nyata dengan terjadinya pertempuran-pertempuran di berbagai daerah yang diduduki tentara Sekutu dengan para pemuda setempat sehingga kebutuhan akan segera dibentuknya tentara reguler yang mampu menghadapi musuh itu semakin mendesak.
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam sidangnya tanggal 22 Agustus 1945 memutuskan untuk membentuk tiga badan sebagai wadah untuk menyalurkan potensi perjuangan rakyat. Badan-badan itu adalah Komite Nasional Indonesia (KNI), Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Badan Keamanan Rakyat (BKR).
BKR sebenarnya merupakan bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) yang pada awalnya bernama Badan Pembantu Prajurit (BPP) dan kemudian menjadi Badan Pembantu Pembelaan (BPP). Kedua badan ini sudah ada pada zaman Jepang dan bertugas memelihara kesejahteraan anggota-anggota tentara Pembela Tanah Air (PETA) dan Heiho. Setelah PETA dan Heiho dibubarkan Jepang pada tanggal 18 Agustus 1945, tugas untuk menampung bekas anggota PETA dan Heiho ditangani oleh BPKKP.
Pembentukan BKR merupakan perubahan dari hasil sidang PPKI 19 Agustus 1945 yang telah memutuskan untuk membentuk tentara kebangsaan. Akibat penyesuaian bidang perjuangan yang ditempuh, muncul beberapa nama sesuai dengan bidang tugas pengabdian seperti BKR Laut, BKR Kereta Api, BKR Pos, dan BKR Udara.
119
bab5-6 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 119 7/10/12 2:16 PM

Pemerintah RI mengumumkan pembentukan BKR pada tanggal 23 Agustus 1945. Presiden Soekarno dalam pidatonya menyerukan kepada bekas tentara PETA, Heiho, Kaigun Heiho dan para pemuda lainnya untuk masuk dalam BKR dan bersiap-siap untuk dipanggil sebagai prajurit tentara kebangsaan jika saatnya tiba. Dalam waktu singkat di daerah-daerah telah berdiri BKR. Di Jakarta, sekelompok pemuda bekas PETA membentuk kantor BKR Pusat, yang dipimpin Kasman Singodimedjo dan Kaprawi sebagai sekretaris. BKR-BKR tersebut kemudian menjelma menjadi badan-badan pelopor revolusi bersenjata yang memimpin perebutan-perebutan kekuasaan sipil dan militer dari Jepang. Dengan diumumkannya BKR, maka beberapa daerah mulai membentuk BKR sendiri seperti di Jakarta dipimpin oleh Moefreini, di Bogor dipimpin oleh Muslihat, di Karesidenan Priangan dipimpin oleh Aruji Kartawinata, dan di Kediri dipimpin oleh R. Soerahmad, dan lain-lainnya.47
Pengumuman terbentuknya BKR tidak serta merta diketahui oleh semua kekuatan di daerah sehingga terlanjur terbentuk satuan-satuan di Sumatera Timur, Palembang dan Aceh yang telah mendirikan organisasi-organisasi seperti Angkatan Pemuda Indonesia (API) di Aceh dan Penjaga Keamanan Rakyat (PKR) di Palembang.
Para pemimpin BKR juga menjadi anggota Komite Nasional yang ikut bahu-membahu dalam memecahkan masalah-masalah yang timbul di daerahnya. BKR bukanlah angkatan bersenjata reguler, melainkan suatu korps perjuangan bersenjata yang ikut mendorong dan memimpin perjuangan dalam memutar roda revolusi pada awal kemerdekaan. Selain unsur darat, di dalam BKR juga terdapat unsur laut dan udara. Unsur laut berasal dari para bekas Kaigun Heiho dan para pemuda yang bekerja pada obyek-obyek vital di pelabuhan dan jawatan-jawatan pelayaran yang membentuk BKR Penjaga Pantai. Sementara itu para pemuda bekas anggota kesatuan penerbangan Jepang seperti Rikugun Koku Butai, Kaigun Koku Butai membentuk BKR Udara.
Walaupun secara resmi BKR adalah aparat untuk menjaga keamanan setempat, namun karena desakan situasi pada saat itu BKR mempelopori perebutan senjata dari tangan tentara Jepang. Selain BKR, terdapat juga Badan Perjuangan yang merupakan organisasi-organisasi yang didirikan para pemuda dengan tujuan ikut mempertahankan kemerdekaan. Sebagian badan perjuangan mempunyai seksi yang dipersenjatai yang lazimnya disebut laskar. Beberapa badan perjuangan sudah berdiri sebelum pemerintah membentuk tentara resmi, namun perkembangannya semakin marak setelah pemerintah
47 Banyak tokoh BKR yang kemudian berjuang sebagai laskar, berasal dari para tokoh masyarakat dan juga para jagoan di jaman kolonial. Bahkan Imam Syafe”i alias bang Pi”ie, pentolan bandit kawasan Pasar Senen dengan organisasinya Oesaha Pemoeda Indonesia (OPI) sempat menjabat sebagai Menteri Negara Keamanan Rakyat.
120
bab5-6 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 120 7/10/12 2:16 PM

mengizinkan didirikannya partai-partai politik. Hampir setiap partai politik besar mempunyai badan perjuangan masing-masing yang dengan sendirinya menganut ideologi partai yang menaunginya.
Menjelma menjadi Tentara Keamanan RakyatSituasi keamanan negara pasca Proklamasi Kemerdekaan semakin tak terkendali, mengingat hampir di semua kota terjadi pertempuran menghadapi Jepang maupun Sekutu/tentara NICA. Sementara itu perlawanan yang dilakukan oleh para pemuda pejuang secara sporadis tidak memenuhi sasaran perjuangan sehingga kebutuhan untuk segera mempunyai tentara reguler semakin mendesak. Untuk itu pemerintah mulai merasa perlu membentuk tentara nasional, dengan mengajak para bekas perwira KNIL yang sebelumnya sudah menyatakan bersumpah setia kepada pemerintah RI.
Pada tanggal 5 Oktober 1945 pemerintah mengeluarkan Maklumat Pemerintah tentang pembentukan tentara kebangsaan yang diberi nama Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pada hari berikutnya keluar pengumuman pemerintah mengenai sedang dilakukannya pembentukan tentara kebangsaan untuk menyempurnakan kekuatan RI. Pada tanggal 9 Oktober 1945 Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) mengeluarkan seruan mengenai mobilisasi TKR:
“Untuk menjaga keamanan rakyat pada dewasa ini oleh Presiden Republik Indonesia telah diperintahkan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat. Tentara ini terdiri atas rakyat Indonesia yang berperasaan penuh tanggung jawab atas keamanan masyarakat Indonesia dan guna menjaga kehormatan negara Republik Indonesia”.
Pada tanggal 20 Oktober 1945, pemerintah mengangkat pucuk pimpinan Kementerian Keamanan Rakyat terdiri dari Menteri Keamanan Rakyat ad interim Muhammad Soeljoadikusumo, Pimpinan Tertinggi TKR Soeprijadi, dan Kepala Staf Umum mantan Mayor KNIL Oerip Soemahardjo.
Sampai awal November 1945, TKR tidak mempunyai pimpinan tertinggi karena Soeprijadi tidak pernah muncul untuk menduduki jabatannya. Untuk mengatasi masalah tersebut, pada tanggal 12 November 1945 diadakan konferensi TKR di Yogyakarta. Konferensi dipimpin oleh Kepala Staf Umum TKR Mayor Oerip Soemahardjo dengan acara pemilihan pimpinan tertinggi TKR dan Menteri Keamanan. Dalam konferensi ini terpilih Kolonel Soedirman, Panglima Divisi V, sebagai Pimpinan Tertinggi TKR dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Menteri Keamanan. Hasil pemilihan ini justru memunculkan ketegangan baru antara kubu Amir Syarifuddin-Oerip Soemahardjo dengan kubu Sri Sultan Hamengkubuwono IX-Soedirman karena perbedaan pandangan tentang status dan peran laskar.
121
bab5-6 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 121 7/10/12 2:16 PM

Pada tanggal 18 Desember 1945, pemerintah dengan resmi mengangkat Kolonel Soedirman menjadi Panglima Besar TKR dengan pangkat Jenderal dan Mayor Oerip Soemahardjo diangkat menjadi Kepala Staf Umum TKR dengan pangkat Letnan Jenderal.48 Disusunlah Markas Tertinggi TKR (MT-TKR) di Yogjakarta. Kemudian Letnan Jenderal Oerip Soemahardjo menyusun Markas Besar Umum (MBU) yang merupakan bagian dari MT-TKR. Susunan organisasi MT-TKR dan komandemen-komandemennya sebagai berikut:
1. Markas Tertinggi TKR.2. Markas Besar Umum TKR terdiri dari Bagian Administrasi, Bagian Keuangan,
Bagian Persenjataan, Bagian Perhubungan, Bagian Kesehatan, Bagian Urusan Kereta Api, Bagian Pendidikan, Bagian Perlengkapan, dan Bagian Penyelidikan.
3. Komandemen I Jawa Barat terdiri dari ; Divisi I di Banten dan Bogor; Divisi II di Jakarta dan Cirebon; serta Divisi III di Priangan.
4. Komandemen II Jawa Tengah terdiri dari ; Divisi IV di Pekalongan, Semarang, Pati; Divisi V di Kedu dan Banyumas; Divisi X Istimewa di Surakarta; serta, Divisi IX Istimewa di Yogjakarta.
5. Komandemen III Jawa Timur terdiri dari ; Divisi VI di Madiun dan Kediri; Divisi VII di Bojonegoro, Surabaya, dan Madiun; serta Divisi VIII di Malang dan Besuki.
6. Komandemen Sumatera terdiri dari ; Divisi I di Sumatera Selatan bagian selatan dan barat; Divisi II di Sumatera Selatan bagian utara dan timur; Divisi III di Sumatera Barat, Riau dan kepulauannya; Divisi IV di Sumatera Timur; Divisi V di Aceh; dan, Divisi VI di Tapanuli dan Nias.
Dengan terbentuknya beberapa divisi tersebut (istilah divisi merupakan awal terbentuknya Kodam), maka TKR dari unsur Darat berasal dari BKR di Jawa dan sebagian di Sumatera yang saat itu terbentuk pada awal kelahiran BKR. Pada konteks ini juga BKR Laut dan BKR Udara menjadi inti TKR. Pada tanggal 15 November 1945, BKR unsur laut disahkan menjadi TKR Laut. Sesuai dengan perubahan BKR
48 Mayor Oerip Soemahardjo adalah tokoh yang berperan besar dalam pembentukan organisasi tentara di masa awal revolusi. Beserta sekelompok pejabat militer muda yang telah menerima pelatihan militer untuk Corps Reserve Officieren (CORO), ia tidak hanya menyerap pandangan umumnya para perwira KNIL tetapi juga pandangan konvensional “Barat” mengenai organisasi militer profesional yang seharusnya tidak diambil alih rakyat sipil.
122
bab5-6 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 122 7/10/12 2:16 PM

menjadi TKR pada tanggal 5 Oktober 1945, BKR Udara pun otomatis menjadi TKR Udara yang pada awalnya dikenal dengan nama TKR Jawatan Penerbangan. Pada tanggal 17 Desember 1945, Panglima Divisi Yogjakarta secara resmi menyerahkan Pangkalan Udara Maguwo beserta personel dan materiil penerbangan kepada Markas Besar Umum Penerbangan.
Berubah Menjadi Tentara Keselamatan RakyatAkhir tahun 1945 muncul ide di kalangan MT-TKR untuk mengubah nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat dengan singkatan tetap TKR. Perubahan nama dari keamanan menjadi keselamatan ditujukan untuk memperdalam dan memperluas tugas tentara dalam arti yang lebih luas. Pada tanggal 7 Januari 1946 keluarlah Penetapan Pemerintah No. 2/SD 1946 tentang penggantian nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat dan nama Kementerian Keamanan menjadi Kementerian Pertahanan. Markas Tertinggi TKR kemudian mengeluarkan pengumuman bahwa mulai tanggal 8 Januari 1946 nama Tentara Keamanan Rakyat diganti dengan nama Tentara Keselamatan Rakyat.
Berubah Menjadi Tentara Republik IndonesiaNama Tentara Keselamatan Rakyat tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 26 Januari 1946 pemerintah mengeluarkan maklumat mengganti nama Tentara Keselamatan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Perubahan nama tersebut berdasarkan Surat Penetapan Pemerintah 1946 No. 4/SD, yang menetapkan; 1) Nama Tentara Keselamatan Rakyat dahulu Tentara Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Republik Indonesia; 2) Tentara Republik Indonesia adalah satu-satunya organisasi militer negara Republik Indonesia; 3) Tentara Republik Indonesia akan disusun atas dasar militer internasional; 4) Tentara Keselamatan Rakyat yang sekarang, yang mulai hari pengumuman maklumat disebut Tentara Republik Indonesia akan diperbaiki susunannya atas dasar dan bentuk ketentaraan yang sempurna; 5) Untuk melaksanakan pekerjaan yang disebut di dalam Fatsal 4, maka oleh pemerintah akan diangkat sebuah panitia. Panitia terdiri dari para ahli militer dan ahli yang dianggap perlu.
Sesuai dengan maklumat tersebut, maka susunan organisasi TRI melalui Penetapan Presiden pada tanggal 23 Februari 1946 disempurnakan oleh sebuah Panitia Besar Penyelenggara Organisasi Tentara. Anggota panitia tersebut adalah Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo, Komodor Suryadarma, Jenderal Mayor Didi Kartasasmita, Jenderal Mayor drg. Mustopo, Kolonel Sutirto, Kolonel Sunjoyo, Kolonel Holand
123
bab5-6 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 123 7/10/12 2:16 PM

Iskandar, Mayor Simatupang, Prof. Supomo, dan Prof. Roosseno. Hasil kerja panitia tersebut diumumkan pada tanggal 17 Mei 1946 di antaranya adalah bentuk Kementerian Pertahanan dan Ketentaraan, kekuatan dan organisasi tentara, peralihan dari keadaan TKR ke keadaan susunan TRI, dan kedudukan laskar-laskar dan barisan-barisan bersenjata. Sebagai konsekuensinya jumlah divisi TRI diperkecil, yang semula di Jawa terdapat 10 divisi diperkecil menjadi 7 divisi dan 3 brigade di Jawa Barat serta 3 divisi di Sumatera. Selain itu juga memberikan wadah kepada Badan Perjuangan dan laskar-laskar yang tidak mau menggabungkan diri kepada TRI, untuk masuk ke dalam sebuah biro khusus dalam Kementerian Pertahanan yaitu Biro Perjuangan. Rivalitas antara tentara dan laskar semakin memanas ketika kedua belah pihak saling mempertanyakan legitimasi pihak yang satu kepada pihak lainnya. 49 Tentara menilai keinginan laskar untuk tetap berada di luar TRI sebagai tindakan pemborosan tenaga prajurit dan persenjataan yang ada, sekaligus menghambat pengembangan organisasi militer yang disusun.
Berubah Menjadi Tentara Nasional IndonesiaDalam perkembangannya kemudian, adanya dua macam pasukan bersenjata yaitu, TRI sebagai tentara reguler, dan Badan Perjuangan sebagai kekuatan rakyat. Kondisi tersebut sangat tidak menguntungkan perjuangan karena Badan Perjuangan dan laskar-laskar tersebut mempunyai haluan politik sesuai dengan partainya masing-masing. Kenyataan itu membuat pemerintah pada tanggal 15 Mei 1947 mengeluarkan Penetapan Presiden untuk mempersatukan kekuatan perjuangan tersebut ke dalam satu organisasi tentara nasional. Perkembangan selanjutnya pada tanggal 7 Juni 1947 pemerintah mengeluarkan Penetapan Presiden yang menyatakan bahwa mulai tanggal 3 Juni 1947 disahkan dengan resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI). TNI merupakan gabungan dari TRI dan seluruh laskar bersenjata, baik yang sudah atau tidak tergabung dalam Biro Perjuangan. Ketetapan Presiden tersebut juga menyatakan bahwa TNI menjalankan tugas kewajiban mengenai siasat dan organisasi, selama proses penyempurnaan TNI sedang berjalan. Semua satuan angkatan perang dan satuan laskar yang melebur ke dalam TNI, diwajibkan taat dan tunduk pada segala perintah dan instruksi yang dikeluarkan oleh pucuk pimpinan TNI.
Pada tanggal 2 Januari 1948 Presiden menandatangani Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1948 yang menyatakan pucuk pimpinan TNI dan Staf Gabungan Angkatan
49 Laskar banyak berasal dan berakar kuat dari komunitas lokal setempat di mana mereka “mendadak” tampil sebagai kelompok revolusioner. Mereka menganggap tentara terlalu menganut sistem dan doktrin yang berasal dari tentara kolonial Belanda dan Jepang. Sebaliknya, tentara yang pernah mendapatkan pelatihan militer profesional dan berstatus resmi, justru menganggap laskar sebagai prajurit yang tidak profesional dan tidak disiplin.
124
bab5-6 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 124 7/10/12 2:16 PM

Perang dibubarkan. Sebagai gantinya dibentuk Staf Angkatan Perang di Kementerian Pertahanan dan mengangkat Jenderal Soedirman sebagai Panglima Besar Angkatan Perang Mobile. Pada tanggal 6 maret 1948 pemerintah mengumumkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1948 tentang Organisasi Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang. Kementerian Pertahanan menyelenggarakan pertahanan negara dalam arti seluas-luasnya. Untuk keperluan itu Kementerian Pertahanan menyelenggarakan Angkatan Perang yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
Kementerian Pertahanan dipimpin oleh Menteri Pertahanan. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibantu oleh Staf Angkatan Perang dan Staf Tata Usaha. Staf Angkatan Perang dipimpin Kepala Staf Angkatan Perang dengan dibantu oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, dan Sekretariat Staf Angkatan Perang. Pada 4 Mei 1948 keluar Penetapan Presiden Tahun 1948 No. 14 tentang pelaksanaan Undang-undang 1948 No. 3. Dalam penetapan tersebut antara lain ditetapkan bahwa mulai tanggal 15 Mei 1948 susunan Kementerian Pertahanan terdiri dari staf-staf dan bagian-bagian seperti yang tercantum dalam Undang-undang. Kesatuan mobile dan teritorial tersusun dalam Komando Jawa dan Komando Sumatera.
Pada tanggal 10 Desember 1950 berdasarkan surat penetapan kementerian Pertahanan No. 126/MP/1949 organisasi Angkatan Darat terdiri dari Kepala Staf, Direktorat, Inspektorat dan Pasukan, Staf Angkatan Darat terdiri dari Staf “G”, Staf “A” dan Staf “Q”, Direktorat Pendidikan, Inspektorat Infanteri dan Senjata Bantuan Angkatan Darat. Kepala Staf Angkatan Darat dan Kepala Staf di bawahnya sebagai berikut ; 1) Kepala Staf AD Kolonel AH. Nasution; 2) Kepala Staf “G” Kolonel Bambang Sugeng; 3) Kepala Staf “Q” Kolonel Hidayat; dan, 4) Kepala Staf “A” Kolonel Suhud.
Pada tanggal 15 Januari 1950, Menteri Pertahanan mengeluarkan surat penetapan nomor 12/MP/50 yang menentukan pembagian teritorium sebagai berikut ; 1) Teritorium Sumut meliputi Aceh, Tapanuli dan Sumatera Timur; 2) Teritorium Sumbar; 3) Teritorium Riau, Bangka dan Belitung; 4) Teritorium Sumsel meliputi Jambi, Bengkulu, Palembang dan Lampung; 5) Teritorium Jabar; 6) Teritorium Jakarta; 7) Teritorium Jateng; 8) Tertorium Jatim; 9) Toritorium Kaltim; 10) Teritorium Sulawesi dan Maluku; dan, 11) Teritorium Sunda Kecil meliputi Bali, Lombok, Sumba, Sumbawa, Flores dan Timor.
125
bab5-6 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 125 7/10/12 2:16 PM

Pada tanggal 28 Juli 1951, berdasarkan surat Keputusan Menteri Pertahanan No D/MP/313/51 mengeluarkan tugas Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) sebagai salah satu unsur APRI meliputi tugas primer adalah tugas pertahanan negara dan tugas sekunder adalah tugas polisional. Sedangkan Susunan organisasi Angkatan Laut terdiri dari tiga bagian:1. Staf Angkatan Laut (SAL) meliputi Staf Operasi, Staf Departemental, Senjata
Bantuan Jawatan dan bagian yang dipimpin oleh Asisten KSAL.2. Dinas-dinas/Pelayanan serta bantuan pendidikan AL. 3. Kesatuan operasi Angkatan Laut (Komando Teritorial Maritim, Komando Mobil).
Berdasarkan surat Kepala Staf Angkatan Udara tanggal 27 April 1950 reorganisasi Angkatan Udara di bagi menjadi tiga fase sebagai berikut ; fase pertama konsolidasi, fase kedua reorganisasi, dan fase ketiga rekontruksi AURI.
Sesudah Pengakuan Kedaulatan tanggal 27 Desember 1949, masalah utama yang dihadapi Angkatan Perang adalah membangun, membina, dan mengembangkan angkatan perang, serta menyempurnakan manajemen organisasi dalam tubuh Angkatan Perang. Tanggung jawab keamanan diserahkan sepenuhnya kepada Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS). Untuk pelaksanaannya, diangkat Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai koordinator keamanan yang memegang kekuasaan tertinggi atas badan kemiliteran dan kepolisian. Pada proses tersebut diberlakukan pemerintahan militer, sedangkan tanggung jawab keamanan daerah diserahkan kepada gubernur militer sekaligus merangkap koordinator keamanan untuk daerah kekuasaannya. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden RIS tanggal 28 Desember 1949, di tingkat pimpinan diangkat ; 1) Kepala Staf Angkatan Perang Letnan Jenderal Soedirman; 2) Pejabat Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel T.B. Simatupang; 3) Kepala Staf Angkatan Darat Kolonel A.H. Nasution; 4) Kepala Staf Angkatan Laut Kolonel R. Subijakto; dan, 5) Kepala Staf Angkatan Udara Komodor Udara S. Suryadarma.
Berbagai perubahan-perubahan organisasi tersebut tidak terlepas dari pertarungan konsep pembangunan TNI. Di satu pihak kelompok berlatar belakang KNIL (T.B. Simatupang, A.H. Nasution, Subiyakto, dan Suryadarma) yang didukung oleh Moh. Hatta, dan pihak lainnya yang didukung Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang menginginkan pembentukan tentara yang profesional (the new form of army). Pihak berikutnya, kelompok dari PETA dan laskar yang tidak menginginkan adanya perubahan dalam organisasi Angkatan Perang dan menentang pengurangan jumlah Angkatan Perang. Kelompok ini didukung Soekarno, Moh. Yamin, dan kelompok Partai Murba. Partai-partai politik bertarung di medan parlemen berebut pengaruh terhadap Angkatan Perang sehingga banyak perwira terpengaruh oleh sasaran-sasaran praktis partai politik
126
bab5-6 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 126 7/10/12 2:16 PM

tertentu. Akibatnya terjadi peristiwa 17 Oktober 1952, yang dinilai oleh sebagian kalangan sebagai bentuk perlawanan TNI AD terhadap pemerintah.
Keadaan pemerintahan sampai dengan 1959 semakin jauh dari harapan. Permasalahan-permasalahan menonjol yang belum dapat dipecahkan antara lain penyelesaian konstitusi negara yang berlarut-larut dan perpecahan dalam kepemimpinan nasional, kemerosotan ekonomi dan korupsi yang merajalela, keamanan yang semakin memburuk dan pembebasan Irian Barat yang belum selesai, serta pergolakan di lingkungan APRI dan partai politik. Hal tersebut mendorong APRI untuk mencari jalan keluar mengatasi kesulitan dengan upaya mencari sistem kenegaraan yang lebih cocok dan mencari sistem militer yang sesuai kepribadian kondisi bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang.
Dalam pertemuan-tertemuan pada Rapat Collegiaal (Raco) tanggal 25 Februari 1955 di Yogyakarta dicapai kesepakatan yang tertulis dalam Piagam Keutuhan Angkatan Darat RI dan diteruskan dengan suatu ikrar kesetiaan di depan makam Panglima Besar Jenderal Soedirman, di mana Presiden dan Wapres bertindak sebagai Inspektur Upacara pada saat itu. Rapat tersebut membahas tiga masalah pokok yakni, keutuhan dan persatuan Angkatan Darat, penyelesaian kasus 17 Oktober 1952 dan pembangunan Angkatan Darat. Reorganisasi TNI AD 1957 menghapuskan struktur tentara dan teritorium diganti dengan Komando Daerah Militer (Kodam) dan penyelesaian konflik pusat-daerah yang berpengaruh pada organisasi militer.
Berubah Menjadi Angkatan Bersenjata Republik IndonesiaMasa reorganisasi yang juga cukup memberikan pengaruh pada perkembangan militer Indonesia adalah ketika terjadi penyatuan angkatan-angkatan dan Polri dalam satu wadah yang kemudian dikenal dengan nama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 225/Plt/1962 tanggal 21 Juni 1962. Penyatuan ini pada hakekatnya merupakan sikap penting dalam perjuangan integrasi ABRI yang senantiasa dihambat dan dihalang-halangi oleh kekuatan-kekuatan politik di luar ABRI.
Usaha ke arah pembentukan satu ABRI tersebut sudah dimulai sejak masa Ir. Djuanda menjadi Menteri Pertama, dengan dibentuknya panitia yang dipimpin oleh Deputi Menteri Keamanan Nasional, Hidayat, yang anggotanya terdiri dari KSAD, KSAL, KSAU dan KSAK. Panitia ini bertugas menyusun struktur organisasi. Dalam konsep yang disusun panitia, terdapat jabatan Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab) yang membawahi Kepala-kepala Staf Angkatan dan Polri.
127
bab5-6 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 127 7/10/12 2:16 PM

Selanjutnya konsep tersebut disampaikan pada Presiden Soekarno, namun Presiden berkeinginan lain terhadap struktur angkatan bersenjata ke depan.
Dengan konsep Samenbundeling Van Alle Krachten (gotong royong) Presiden Soekarno melakukan reorganisasi dan integrasi TNI AD, AL, AU, dan Polri menjadi ABRI. Soekarno membentuk Komando Operasi Tertinggi (KOTI). ABRI dipimpin langsung oleh Presiden dan para Panglima dari AD, AL, AU, dan AK menjadi menteri. Ancaman nyata adalah musuh yang berada di Irian Barat sehingga Irian Barat harus dibebaskan dari kolonialisasi Belanda.
Presiden Soekarno menginginkan agar dalam struktur organisasi angkatan bersenjata, Presiden merupakan panglima tertinggi angkatan bersenjata yang secara langsung membawahi semua angkatan dan polisi. Panglima tertinggi mempunyai seorang Kepala Staf Angkatan Bersenjata (KSAB) yang hanya mempunyai wewenang pada bidang administrasi tetapi tidak memegang komando operasi. Beberapa pengamat pada waktu itu menilai bahwa struktur tersebut lebih dimaksudkan agar Presiden dengan mudah dapat merangkul salah satu angkatan ke pihaknya apabila ia memerlukan dukungan untuk kepentingan politiknya.
Selanjutnya, muncul Keputusan Presiden No. 225/Plt/1962 yang menetapkan pucuk pimpinan angkatan bersenjata adalah Presiden/Panglima Tertinggi (Pangti) yang memegang kekuasaan tertinggi dan dibantu oleh Staf Angkatan Bersenjata yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Bersenjata. Kepala Staf Angkatan Bersenjata dibantu oleh 3 orang deputy, yaitu deputy operasi, deputy pembinaan, dan deputy khusus. Para deputy membawahi direktorat-direktorat. Sedangkan susunan organisasi Angkatan Darat, laut, udara, dan kepolisian akan diatur keseragamannya atas dasar adanya unsur-unsur pembinaan dan operasional. Kemudian setelah reshuffle Kabinet Karya menjadi Kabinet Kerja pada tahun 1962, para Kepala Staf Angkatan diganti menjadi Panglima Angkatan. Sebagai pembantu Presiden, para panglima angkatan diberi jabatan menteri. Struktur baru yang dikehendaki Presiden adalah adanya panglima tertinggi dan panglima angkatan. Sebutan mereka adalah Menteri/Panglima Angkatan dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata adalah juga Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan disebut Menko Hankam/ Kasab.
Sesudah meninggalnya Menteri Pertama Ir. Djuanda, susunan kabinet diubah menjadi Presidium Kabinet dengan tiga orang wakil perdana menteri. Wakil Menteri Pertama berubah menjadi Menteri Koordinator (Menko). Dengan adanya menko ini Staf Angkatan Bersenjata (SAB) praktis dibatasi wewenangnya di bidang pembinaan.
128
bab5-6 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 128 7/10/12 2:16 PM

Di bidang operasi, Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Keputusan No. 142 tahun 1963 tanggal 19 Juli 1963 tentang Pembentukan KOTI dengan tugas terutama pengamanan pelaksanaan program pemerintah. KOTI dipimpin langsung oleh Presiden/Pangti ABRI. Dengan adanya perkembangan ini, maka komando ABRI secara de jure dan de facto dipegang oleh Presiden.
Reorganisasi 1962 mempunyai dampak negatif, beberapa di antaranya adalah disintegrasi antar angkatan yang bersumber pada perbedaan institusi intelijen, ketimpangan anggaran belanja, pembinaan pasukan komando/elite, doktrin, dan lain-lain. Presiden sebagai Pangti ABRI juga membentuk lembaga-lembaga yang berfungsi sama dengan angkatan, ada 6 lembaga pertahanan keamanan yang menyelenggarakan fungsi hampir sama, yaitu KOTI, Kompartemen Hankam, Departemen/Angkatan Darat, Departemen/Angkatan Laut, Departemen/Angkatan Udara, dan Departemen/Angkatan Kepolisian. Masing-masing lembaga ini berdiri sendiri tanpa koordinasi dan integrasi yang tegas. Kebijakan Presiden tersebut menyebabkan organisasi ABRI terkotak-kotak dan terperangkap dengan wawasan matra masing-masing. Kondisi ini menyebabkan terjadi disintegrasi dalam tubuh ABRI karena masing-masing membentuk doktrin sendiri-sendiri. Akibat negatif lainnya adalah rivalitas antar angkatan dan pengaruh partai/ideologi politik telah menyusup sampai ke prajurit bawahan.
Reorganisasi ABRI tahun 1967 menetapkan pengintegrasian ulang Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian benar-benar dalam satu wadah yaitu ABRI. Untuk menyempurnakan dan memperjelas fungsi angkatan dan struktur organisasi ABRI, Menteri Utama Hankam Jenderal TNI Soeharto memerintahkan Mayor Jenderal M.M.R. Kartakusuma, Kepala Staf Hankam untuk menyusun organisasi ABRI baru. Hasilnya pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Presiden No. 132 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur bidang Pertahanan Keamanan. Dalam keputusan ini organisasi ABRI dibagi atas 2 tingkat yaitu tingkat departemen dan angkatan. Pemegang kekuasaan tertinggi angkatan bersenjata dan pimpinan Hankam adalah Presiden dibantu oleh Menhankam/Pangab. ABRI merupakan bagian organik Departemen Hankam yang meliputi Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), Angkatan Udara (AU), dan Angkatan Kepolisian (AK).
Hampir 1 tahun ABRI mengaplikasikan organisasi berdasarkan Keputusan Presiden tersebut, namun dianggap belum berhasil menciptakan organisasi yang kompak karena masih terlalu luas, kurang efisien dan efektif. Pada tanggal 4 Oktober 1969 dikeluarkanlah Surat Keputusan Presiden No. 79 Tahun 1969 tentang Penyempurnaan Organisasi ABRI.
129
bab5-6 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 129 7/10/12 2:16 PM

Refungsionalisasi dan reorganisasi dilakukan berdasarkan hakekat ancaman, di mana Kepemimpinan ABRI meskipun dirangkap oleh Menhan tetapi komando dan pengendalian diperluas dalam organisasi Kowilhan.
Tujuan penyempurnaan ini adalah agar akhir tahun 1973 ada landasan dan titik tolak pokok bagi pembangunan sistem Hankamnas dan ABRI. Selain itu penyempurnaan ini diharapkan agar dalam waktu yang tidak terlalu lama ABRI memiliki suatu sistem Hankamnas yang modern, baik aparatur maupun doktrinnya. Prinsip dasar penyempurnaan organisasi ABRI tahun 1969 adalah penentuan dan pembagian fungsi yang dilaksanakan sebagai wujud fungsionalisasi sesuai dengan kemampuan dan hakekat angkatan. Konsekuensinya adalah pembedaan fungsi antara angkatan perang dengan kepolisian, sehingga ABRI terdiri dari Angkatan Perang dan Kepolisian RI. Tingkat departemen terdiri dari eselon pimpinan yaitu Menhankam/Pangab dan Wapangab. Eselon staf terdiri dari badan staf utama meliputi Staf Umum, Staf Departemental, Staf Kekaryaan, Staf Perencanaan Umum, Inspektorat Jenderal Pengawasan Keuangan, dan Staf Pribadi. Eselon Angkatan terdiri dari TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan Kepolisian Negara yang masing-masing dipimpin Kepala Staf Angkatan dan Kapolri.
Berdasarkan pertimbangan bahwa belum tercapainya kemantapan integrasi fungsi-fungsi pertahanan, baik dalam segi pokok-pokok organisasi maupun prosedur kerjanya, pemerintah menganggap perlu menyempurnakan kembali organisasi ABRI. Pada tahun 1974 dikeluarkanlah Keputusan Presiden No. 7 tahun 1974 tanggal 18 Februari 1974 yang menyebutkan bahwa fungsi Hankamnas pada dasarnya diselenggarakan oleh Departemen Pertahanan Keamanan (Dephankam). Tugas pokoknya menyelenggarakan kebijakan dan pembinaan ketahanan nasional bidang Hankamnas, menyelenggarakan pimpinan dan pembinaan ABRI sebagai inti kekuatan Hankamnas dan kekuatan sosial serta menyelenggarakan, memimpin dan mengendalikan operasi-operasi Hankam.
Dephankam disusun dalam bentuk organisasi garis dan staf, dibagi dalam 2 tingkat yaitu tingkat departemen dan tingkat komando utama. Tingkat departemen berbentuk eselon pimpinan terdiri dari Menhankam/Pangab dan Wapangab. Eselon pembantu pimpinan terdiri dari Kepala Staf Operasi (Kasops), Kepala Staf Administrasi (Kasmin), Kepala Staf Kekaryaan (Kaskar), dan Inspektorat Jenderal dan Perbendaharaan Dephankam (Irjen Hankam).
Berikutnya, Reorganisasi 1981 menekankan kepada peralihan generasi dari generasi 1945 ke generasi muda yang lebih sejalan dengan program pemerintah untuk mendukung Pembangunan Nasional, dan mengemukanya penurunan kewaspadaan terhadap hakekat ancaman.
130
bab5-6 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 130 7/10/12 2:16 PM

Sebelumnya pertahanan keamanan negara diatur dalam Undang-undang No. 29 tahun 1954. Setelah berlaku beberapa tahun, Undang-undang tersebut dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan RI dan pertumbuhan ABRI serta perkembangan persyaratan pertahanan keamanan negara. Pada tanggal 6 September 1982 Undang-undang Pertahananan Keamanan Negara disetujui oleh DPR, yaitu Undang-undang No. 20/1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI. Untuk melaksanakan Undang-undang tersebut, dikeluarkanlah Keppres No. 46 tahun 1983 tentang Pokok-Pokok dan Susunan Organisasi Dephankam dan Keppres No. 60/1983 tentang Pokok-Pokok dan Susunan Organisasi Angkatan Bersenjata. Terjadi pemisahan antara Dephankam dengan Markas Besar ABRI, sehingga Pangab dapat lebih memusatkan perhatian pada peningkatan kemampuan ABRI dan komando pengendalian operasional. Keppres tersebut menyusun organisasi ABRI menjadi 3 tingkat. Tingkat Mabes ABRI terdiri dari eselon pimpinan oleh Pangab. Eselon pembantu pimpinan terdiri dari Kepala Staf Umum (Kasum), Kepala Staf Sosial Politik (Kassospol), dan Inspektur Jenderal dan Perbendaharaan (Irjen). Tingkat angkatan dan kepolisian negara terdiri dari ; 1) TNI AD; 2) TNI AL; 3) TNI AU; dan, 4) Polri. Pada tingkat komando utama operasional terdiri dari: Komando Strategi Nasional (Kostranas), Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas), dan Komando Wilayah Pertahanan (Kowilhan).
Pada Perencanaan Strategis Pembangunan Kekuatan ABRI (Renstra Bangkuat ABRI) tahun 1984, mencantumkan antara lain bahwa untuk dapat mengawal dan ikut serta dalam pembangunan jangka panjang tahap kedua yang menjangkau kurun waktu tahun 2000-an, diperlukan postur ABRI yang sesuai dengan tuntutan zaman. Tujuannya adalah untuk membentuk ABRI yang makin kuat dan kompak, siap menghadapi dinamika lingkungan strategis dalam dan luar negeri yang makin kompleks. Pada reorganisasi ABRI tahun 1984, Kowilhan dan Kostranas dilikuidasi sehingga fungsi kedua komando tersebut dilimpahkan kepada Kodam dan Kostrad dengan didukung oleh Komando Armada TNI AL dan Komando Operasi TNI AU. Reorganisasi ini sekaligus memperkecil jumlah Kodam disesuaikan pada struktur wilayah diubah berdasarkan strategi pertahanan pulau.
Dengan perkembangan tersebut jumlah Kodam di seluruh Indonesia yang semula 17 Kodam menjadi 10 Kodam termasuk 1 Kodam di Ibukota Jakarta. Komando Daerah AL (Kodaeral) dan Komando Daerah AU (Kodau) semula masing-masing merupakan Komando Utama (Kotama) TNI AL dan TNI AU dihapuskan dan digantikan dengan penataan sistem pangkalan yang lokasinya didasarkan pada pertimbangan menempati
131
bab5-6 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 131 7/10/12 2:16 PM

daerah yang mempunyai nilai strategis dan taktis tinggi. Komando Operasi TNI AL dikelompokkan menjadi Komando Armada RI Kawasan Barat dan Komando Armada RI Kawasan Timur. Sedangkan Komando Operasi TNI AU menjadi Komando Operasi TNI AU I dan Komando Operasi TNI AU II. Komando Daerah Angkatan Kepolisian jumlahnya tetap dipertahankan 17, tetapi sebutannya berubah menjadi Polisi Daerah (Polda) dengan pertimbangan bahwa tugas-tugas kepolisian erat hubungannya dengan tugas-tugas pemerintahan daerah.
Pada tingkat Mabes ABRI organisasi dibagi menjadi 3 eselon yaitu; eselon pembantu pimpinan/staf, eselon pelayanan, dan eselon pelaksana pusat. Hal ini sesuai dengan Keputusan Pangab No. Kep/03/P/XII/1983. Untuk satuan-satuan pada eselon pelayanan didasarkan pada Keputusan Pangab No. Kep/08/P/XII/1983, dan satuan-satuan pada eselon pelaksana pusat didasarkan pada Keputusan Pangab No. Kep/01/P/I/1984.
Sejalan dengan perkembangan pembangunan nasional dan memperhatikan perkembangan internasional, pemerintah menganggap perlu melakukan penyempurnaan organisasi angkatan bersenjata. Penyempurnaan ini dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang optimal untuk mendukung keberhasilan tugas pokok masing-masing angkatan. Pada tanggal 5 Oktober 1992 keluar Keputusan Pangab No. Kep/08/X/1992 tentang Penyempurnaan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur TNI AD, Keputusan Pangab No. Kep/09/X/1992 tanggal 5 Oktober 1992 tentang Penyempurnaan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur TNI AL dan Keputusan Pangab No. Kep/10/X/1992 tanggal 5 Oktober 1992 tentang Penyempurnaan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur TNI AU. Untuk Polri penyempurnaan organisasi didasarkan pada Keputusan Pangab No. Kep/11/X/1992 tanggal 5 Oktober 1992 tentang Penyempurnaan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Polri.
Dalam perkembangan selanjutnya untuk memantapkan Reorganisasi ABRI sesuai dengan tuntutan keadaan, diadakan lagi penyempurnaan terhadap Keputusan Pangab No. Kep/09/X/1992 tanggal 5 Oktober 1992 tentang Penyempurnaan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur TNI AL. Penyempurnaan organisasi TNI AL ini didasarkan pada Keputusan Pangab No. Kep/08/VII/1997 tanggal 9 Juli 1997 tentang Penyempurnaan Organisasi ABRI dan Prosedur TNI AL. Dalam jajaran TNI AU juga diadakan penyempurnaan organisasi sesuai dengan Keputusan Pangab No. Kep/08/VII/ 1997 tanggal 7 Juli 1997. Perkembangan berikutnya Reorganisasi 1998 lebih didorong dari lahirnya konsep Civil Society dan lahirnya paradigma baru, TNI ingin meninggalkan peran politiknya. Pada masa ini dihasilkan pula produk hukum Undang-Undang Pertahanan Negara No. 3 Tahun 2002 dan Undang-Undang TNI No. 34 Tahun 2004.
132
bab5-6 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 132 7/10/12 2:16 PM

Sesungguhnya dalam perkembangan kurun waktu tersebut, TNI yang terdiri dari angkatan-angkatan sesuai matra darat, laut, udara dan kepolisian justru berkembang sesuai dengan kepentingan matra masing-masing sehingga malah timbul persaingan yang tidak sehat antar angkatan.
Kembali Menjadi Tentara Nasional IndonesiaPada era Reformasi 1998, muncul gagasan pemisahan TNI dan Polri. Pemikiran tersebut sebenarnya sudah lama terdapat di kalangan perwira-perwira TNI dan Polri, karena sesuai dengan fungsinya polisi masuk dalam unsur non kombatan. Pemisahan TNI dan Polri dilakukan untuk memperjelas tugas, wewenang dan tanggung jawab TNI dan Kepolisian. Pemisahan Polri dari TNI sebagai bagian dari reformasi bidang pertahanan keamanan agar terwujud profesionalisme pertahanan keamanan negara. TNI bertugas di bidang pertahanan negara dan Polri bertugas di bidang keamanan negara. Sejak tanggal 1 April 1999, Polri secara resmi terpisah dari ABRI. Terpisahnya Polri dari ABRI ini kemudian ditindak lanjuti dengan penggantian nama ABRI kembali menjadi TNI, yang ditetapkan melalui Keputusan Menhankam/Pangab No. Skep/259/P/IV/1999 tanggal 12 April 1999.
Keputusan untuk memisahkan Polri dari ABRI diusulkan kepada pemerintah oleh Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto, mengingat ABRI sedang melakukan redefinisi, reposisi dan reaktualisasi perannya sebagai perwujudan reformasi internal TNI. Selain itu juga terkait dengan masalah penegakkan hukum di Indonesia, keberadaan Polri akan lebih baik bila berada dekat dengan aparat penegak hukum lainnya dalam sistem hukum di Indonesia ketimbang terus berada pada lingkungan ABRI. Selanjutnya untuk membangun masyarakat madani (Civil Society), diperlukan kepolisian yang mandiri agar dapat memperkuat pemerintahan sipil. Sementara keberadaan kepolisian yang menyatu dengan angkatan bersenjata di dunia sebelumnya hanya ada dua yaitu di Indonesia dan Myanmar yang mengikuti Indonesia. Dalam lingkungan dunia internasional konsep tersebut tidak cocok, karena ketika Polri diundang dalam pertemuan internasional bidang kepolisian, anggota Polri seringkali ditolak, karena keberadaannya yang menyatu dengan ABRI.
Lahirnya konsepsi kebijakan strategi Menhankam/Pangab pada Oktober 1998 tentang Paradigma Baru Peran ABRI, merupakan perwujudan dorongan sikap kesadaran ABRI yang menganggap perlu reformasi internal sebagai upaya penataan dan penyempurnaan sistem, doktrin, dan struktural. Hal tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 355/M tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999 tentang Pembentukan Kabinet
133
bab5-6 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 133 7/10/12 2:16 PM

Periode 1999-2004, maka jabatan Menhankam dengan Pangab dipisah. Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut, dilakukanlah perubahan yang mencakup pemisahan jabatan Menhankam dari Pangab, perubahan susunan organisasi Staf Umum ABRI, Staf Sospol ABRI, dan pemisahan organisasi Polri dari ABRI.
Melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1999 tanggal 1 April 1999 tentang langkah-langkah kebijakan dalam rangka pemisahan Polri dari ABRI serta Keputusan Menhankam/Pangab No. Kep/05/P/III/1999 tanggal 31 Maret 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pembinaan Kepolisian RI, maka mulai 1 April 1999 Kepolisian Negara RI secara resmi berpisah dari ABRI. Perubahan ini ditandai dengan upacara militer penyerahan Panji-Panji Polri dari Kasum TNI kepada Sekjen Dephankan yang kemudian menyerahkannya kepada Kapolri.
Paradigma baru TNI merupakan bentuk nyata dari reformasi internal TNI yang dilandasi cara berpikir yang bersifat analitik dan prospektif ke masa depan. Berdasarkan pada pendekatan komprehensif sehingga memunculkan empat paradigma baru peran Sospol TNI yaitu ; 1) Mengubah posisi metode tidak harus selalu di depan; 2) Mengubah dari konsep menduduki menjadi mempengaruhi; 3) Mengubah cara mempengaruhi secara langsung menjadi tidak langsung; dan, 4) Kesediaan untuk melakukan politicial and role sharing dengan komponen bangsa lainnya.
Secara kuantitatif TNI telah dan terus menerus melakukan reformasi internal dan dalam waktu yang relatif singkat telah terjadi perubahan-perubahan yang signifikan antara lain:• Sikap dan pandangan politik ABRI tentang paradigma baru peran ABRI abad
XXI.• Sikap dan pandangan politik ABRI tentang paradigma baru peran Sospol ABRI.• Pemisahan Polri dan ABRI yang telah menjadi keputusan pimpinan ABRI mulai 1
April 1999 sebagai transformasi awal.• Penghapusan Dewan Sosial Politik Pusat (Wansospolplus) dan Dewan Sosial
Politik Daerah (Wansospolda)/tingkat-I.• Perubahan Staf Sosial Politik menjadi Staf Teritorial.• Likuidasi Staf Karyawan (Syawan) ABRI, Kamtibmas ABRI dan Badan Pembina
Kekaryaan (Babinkar) ABRI.• Penghapusan Sospol Kodam (Sospoldam), badan Pembina Kekaryaan Kodam
(Babinkardam), Sospol Korem (Sospolrem) dan Sospol Kodim (Sospoldim).• Penghapusan kekaryaan ABRI melalui keputusan pensiun atau alih status.• Pengurangan jumlah Fraksi ABRI di DPR, DPRD I/II.
134
bab5-6 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 134 7/10/12 2:16 PM

• ABRI tidak akan pernah lagi terlibat dalam politik praktis atau day-to-day politics.
• Pemutusan hubungan organisatoris dengan Partai Golkar dan mengambil jarak yang sama dengan partai politik yang ada.
• Komitmen dan konsisten sikap netralitas ABRI dalam Pemilu.• Perubahan paradigma hubungan ABRI dan Keluarga Besar ABRI.• Revisi piranti lunak berbagai doktrin ABRI disesuaikan era reformasi dan peran
ABRI abad XXI.• Perubahan nama ABRI menjadi TNI.• Perubahan Staf Sospol menjadi Staf Komunikasi Sosial (Komsos).• Pembubaran Badan Koordinasi dan Strategi Nasional (Bakorstanas) dan Badan
Koordinasi dan Strategi Daerah (Bakorstanasda).
5.2.
Pengaruh Dinamika Lingkungan Global terhadap Militer Indonesia
Periode 1945-1949. Perjanjian Wina tahun 1942, menyatakan bahwa negara-negara Sekutu bersepakat untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang diduduki Jepang pada pemilik koloninya masing-masing bila Jepang berhasil diusir dari daerah pendudukannya. Menjelang akhir perang, tahun 1945, sebagian wilayah Indonesia telah dikuasai oleh tentara Sekutu. Australia telah mendaratkan pasukannya di Makassar dan Banjarmasin, sedangkan Balikpapan telah diduduki oleh Australia sebelum Jepang menyatakan menyerah kalah. Sementara Pulau Morotai dan Irian Barat bersama-sama dikuasai oleh pasukan Australia dan AS di bawah pimpinan Jenderal Douglas MacArthur, Panglima South West Pacific Area Command (SWPAC).
Setelah perang usai, tentara Australia bertanggung jawab terhadap Kalimantan dan Indonesia bagian Timur, AS menguasai Philipina dan tentara Inggris dalam bentuk South East Asia Command (SEAC) bertanggung jawab atas India, Burma, Srilanka, Malaya, Sumatra, Jawa dan Indocina. SEAC dengan panglima Lord Mountbatten sebagai Komando Tertinggi Sekutu di Asia Tenggara bertugas melucuti bala tentera Jepang dan mengurus pengembalian tawanan perang dan tawanan warga sipil sekutu Recovered Allied Prisoners of War and Internees (RAPWI). Berdasarkan Civil Affairs Agreement, pada tanggal 23 Agustus 1945 Inggris bersama tentara Belanda mendarat
135
bab5-6 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 135 7/10/12 2:16 PM

di Sabang, Aceh. Tanggal 15 September 1945, tentara Inggris selaku wakil Sekutu tiba di Jakarta, dengan didampingi Dr. Charles van der Plas, wakil Belanda pada Sekutu. Kehadiran tentara Sekutu ini, diboncengi Netherland Indies Civil Administration (NICA) yang dipimpin oleh Dr. Hubertus J van Mook.
Meskipun Inggris datang bersama Belanda tak lama setelah Proklamasi Kemerdekaan tetapi cepat menyadari bahwa Bangsa Indonesia telah bertekad mempertahankan kemerdekaannya yang direbut dari Bala Tentara Jepang. Kenyataan tersebut yang akhirnya memutuskan Inggris menarik pasukannya dari Indonesia setelah terpukul pada pertempuran 10 Nopember 1945 di Surabaya50, Palagan Ambarawa 15 Desember 194551, dan terakhir peristiwa Bandung Lautan Api 23 Maret 1946.
Sepeninggal Inggris, Belanda melancarkan Agresi Militer pertama tahun 1947 dan kedua tahun 1948. Indonesia membalas dengan Serangan Umum 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta yang direncanakan dan dipersiapkan oleh jajaran tertinggi militer di wilayah Divisi III/GM III dengan mengikutsertakan beberapa pucuk pimpinan pemerintah sipil setempat berdasarkan instruksi dari Pangsar Jenderal Soedirman. Serangan militer tersebut berhasil mematahkan moral pasukan Belanda dan membuktikan kepada dunia internasional bahwa TNI - berarti juga RI - masih ada dan cukup kuat, sehingga dengan demikian dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan PBB. Mr. Alexander Andries Maramis, yang berkedudukan di New Delhi menggambarkan betapa gembiranya mereka mendengar siaran radio yang ditangkap dari Burma, mengenai serangan besar-besaran TNI terhadap Belanda. Berita tersebut juga menjadi headlines di berbagai media cetak yang terbit di India.
Setelah mengalami kekalahan berturut-turut dan tekanan dunia internasional, Belanda akhirnya bersedia mengakui kedaulatan Indonesia melalui perundingan di Den Haag, yang dikenal dengan Konferensi Meja Bundar (KMB) dari tanggal 23 Agustus hingga tanggal 2 November 1949. Keberhasilan KMB tidak terlepas dari peranan Komisi Jasa Baik (Komisi Tiga Negara) yang dibentuk pada tanggal 25 Agustus 1947 sebagai reaksi PBB terhadap Agresi Militer Belanda pertama. Komisi ini beranggotakan 3 negara, yaitu Australia (dipilih oleh Indonesia), Belgia (dipilih oleh Belanda) dan AS sebagai pihak netral.
50 Berakhir pada tanggal 28 November 1945, setelah pertempuran di Gunungsari.51 Pertempuran pecah pada tanggal 20 November 1945 dengan kekuatan 19 batalion TKR dan beberapa batalion dari laskar yang bertempur silih berganti. Setelah gugurnya Letkol Isdiman, pimpinan pasukan diambil alih oleh Kolonel Soedirman hingga pertempuran terakhir di Banyubiru. Pertempuran ini mempunyai arti penting dan diakui Inggris sebagaimana pertempuran di Surabaya, bahwa pasukan Indonesia sulit ditaklukkan meskipun Inggris sudah mengerahkan seluruh kekuatannya.
136
bab5-6 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 136 7/10/12 2:16 PM

Mencermati komisi tersebut dan jalannya KMB, maka boleh dikatakan Belanda mendapat tekanan dari “pihak Barat” untuk segera mengakui kedaulatan Indonesia. AS dan Inggris sebenarnya juga telah mengakui terlebih dahulu kedaulatan RI sejak 1947, sedangkan Australia merupakan salah satu pendukung utama RI pada masa-masa mempertahankan kemerdekaan. Australia bahkan juga berpartisipasi dalam Konferensi New Delhi pada tanggal 20-25 Januari 1949. Salah satu hasil KMB yang kelak menjadi sengketa berikutnya adalah perbedaan kepentingan antara Indonesia dan Belanda. Indonesia ingin agar semua bekas daerah Hindia Belanda menjadi wilayah resmi Indonesia, sementara Belanda masih ingin menjadikan Irian Barat negara terpisah karena perbedaan etnis. Konferensi ditutup tanpa keputusan mengenai hal ini sehingga pasal 2 menyebutkan bahwa Irian Barat sementara belum menjadi bagian dari serah terima, dan bahwa masalah ini akan diselesaikan dalam waktu satu tahun.
Periode 1949-1956. Pada periode Perang Dingin, Indonesia tidak ingin berpihak kepada salah satu blok. Oleh sebab itu Presiden Soekarno menggagas Gerakan Non Blok (GNB) yang diprakarsai dari sebuah Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika yang diadakan di Bandung pada tahun 1955. Di sana, negara-negara yang tidak berpihak pada blok tertentu mendeklarasikan keinginan mereka untuk tidak terlibat dalam konfrontasi ideologi Barat-Timur. Selain Presiden Soekarno, pendiri gerakan yang lain adalah Josip Broz Tito, presiden Yugoslavia, Gamal Abdul Nasser presiden Mesir, Pandit Jawaharlal Nehru perdana menteri India, dan Kwame Nkrumah dari Ghana. Gerakan ini sempat kehilangan kredibilitasnya pada akhir tahun 1960-an ketika anggota-anggotanya mulai terpecah dan bergabung bersama blok lain, terutama Blok Timur. Meskipun masih bertahan hingga kini, gerakan ini kemudian terpecah sepenuhnya pada masa invasi Uni Sovyet terhadap Afghanistan tahun 1979.
Periode 1956-1962. Hubungan baik Indonesia dengan pihak Barat akhirnya memburuk setelah Indonesia menunjukkan sikap politik luar negerinya ketika terjadi Perang Arab-Israel tahun 1956. Perang tersebut merupakan lanjutan dari perang di tahun 1948 di mana tentara Israel berhasil memenangkan perang melawan Arab, termasuk Mesir. Negosiasi perdamaian setelah perang gagal, ditambah dengan meningkatnya ketegangan perbatasan antara Israel dan tetangganya, menyebabkan permusuhan antara Arab dan Israel tetap membara.
137
bab5-6 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 137 7/10/12 2:16 PM

Terinspirasi oleh hasil KTT Asia Afrika, maka Gamal Abdul Nasser menasionalisasi Terusan Suez pada tanggal 26 Juli 1956. Terusan Suez yang semula berstatus internasional sepenuhnya dianggap milik Bangsa Mesir. Tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran serius yang segera mendapat reaksi dari Inggris dan Perancis. Bahkan Perancis sebenarnya juga ingin “menghukum” Mesir karena membantu pemberontakan Maroko dan Aljazair terhadap kolonisasi Perancis. Kedua negara Eropa yang mempunyai kepentingan dengan Terusan Suez berencana secara bersama-sama akan menyerang Mesir memanfaatkan permusuhan Arab-Israel. AS sebagai negara adidaya dan juga merupakan sekutu Inggris dan Perancis, justru mencoba menghindarkan penyerangan tersebut. Walaupun kalah perang pada akhirnya, namun Mesir menang dalam hal politik. Tekanan diplomatik dari AS dan Uni Sovyet memaksa Inggris, Perancis dan Israel untuk mundur dari Semenanjung Sinai. AS takut akan adanya perang yang lebih luas setelah Uni Sovyet dan negara-negara Pakta Warsawa lainnya mengancam untuk membantu Mesir dan melancarkan serangan roket ke London, Paris dan Tel Aviv.
AS meminta invasi dihentikan dan mensponsori resolusi di Dewan Keamanan PBB yang meminta gencatan senjata. Pasukan perdamaian PBB pertama di bawah komando UNEF dibentuk untuk mengawasi wilayah demiliterisasi, dan Kontingen Garuda Indonesia tiba pada tanggal 8 Januari 1957.52 Presiden Soekarno secara berani dan terbuka menyatakan politik Bebas Aktif sebagai wujud partisipasi dalam menyelesaikan Krisis Suez dengan bersedia menempatkan pasukan TNI sebagai penjaga perdamaian di wilayah Mesir. Pengiriman pasukan penjaga perdamaian oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi Krisis Suez juga untuk menunjukkan solidaritas sebagai sesama negara yang baru merdeka. Sikap politik tersebut juga menandai berakhirnya hubungan dengan Barat sekaligus dimulainya hubungan dengan Timur. Berdasarkan keputusan KMB, semestinya pada akhir tahun 1950 sudah ada upaya Belanda untuk mengembalikan Irian Barat kepada pihak Indonesia. Akan tetapi, tampaknya keputusan KMB yang
52 Kontingen Garuda I dipimpin Letkol Inf Hartoyo, yang kemudian digantikan oleh Letkol Inf Suadi Suromiharjo, sedangkan wakilnya Mayor Inf Soediono Suryantoro. Berkekuatan 559 prajurit terdiri dari gabungan Resimen Infanteri-17 Territorium (TT) IV/Diponegoro dan Resimen Infanteri-18 TT V/Brawijaya diangkut dengan pesawat C-124 Globe Master dari U. S. Air Force menuju Beirut, Libanon. Dari Beirut, pasukan dibagi dua, sebagian menuju ke Abu Suweir dan sebagian lain ditempatkan di Al Sandhira, selanjutnya pasukan yang di Al Sandhira dipindahkan ke Gaza, sepanjang perbatasan Mesir dan Israel, sedangkan kelompok Komando berada di Rafah.
138
bab5-6 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 138 7/10/12 2:16 PM

berkaitan dengan Irian Barat tidak berjalan lancar. Belanda tampak ingin tetap mempertahankan Irian Barat. Oleh karena itulah, Indonesia berusaha mengembalikan Irian Barat melalui upaya diplomasi dan cara-cara militer terhadap Belanda.
Tanggal 17 Agustus 1960 Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda dan untuk menghadapi konfrontasi, pemerintahan melakukan pembelian berbagai Alutsista dari luar negeri, seperti dari Uni Sovyet dan negara-negara lain dari Blok Timur. Puncaknya, pada tanggal 19 Desember 1961 melalui rapat umum di Yogyakarta, Presiden Soekarno mencanangkan Trikora. Dua bulan kemudian, Operasi Jaya Wijaya dilancarkan. Dunia internasional mulai khawatir dan AS mulai menekan Belanda agar mau berunding. Ellswoth Bunker, seorang diplomat AS ditunjuk sebagai penengah, yang selanjutnya mengusulkan pokok-pokok penyelesaian secara damai. Berdasarkan usulan-usulan tersebut, maka pada tanggal 15 Agustus 1962 tercapailah persetujuan antara Indonesia dan Belanda yang dikenal dengan Persetujuan New York.53 Belanda angkat kaki dari Irian Barat.
Periode 1962-1966. Konfrontasi Indonesia-Malaysia atau yang lebih dikenal sebagai Dwikora adalah sebuah pertikaian mengenai masa depan Malaya, Brunei, Sabah dan Sarawak yang terjadi antara Federasi Malaysia dan Indonesia. Konfrontasi ini berawal dari keinginan Federasi Malaya yang lebih dikenal sebagai Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1961 untuk menggabungkan Brunei, Sabah dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia.
53 Pada saat pengakuan kedaulatan Indonesia di Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949 di Den Haag, masalah Papua bagian barat dinyatakan akan diselesaikan dalam waktu satu tahun sejak KMB. Tetapi ke-nyataannya sampai tahun 1961 Belanda tak kunjung menyelesaikannya. Presiden Soekarno menguman-dangkan Trikora dan menggelar operasi militer untuk merebut Papua bagian barat dari kekuasaan Belanda. Operasi Jayawijaya adalah operasi militer terbesar yang digelar Indonesia dengan pengerahan peralatan militer tercanggih pada jaman itu yang banyak dibeli dari Uni Sovyet. Setelah pertempuran Laut Aru pada tanggal 15 Januari 1962, AS mendesak Belanda untuk mengadakan perundingan dengan Indonesia karena khawatir melihat adanya kemungkinan Uni Sovyet makin kuat campur tangan dalam persoalan terse-but. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Adam Malik dan Belanda oleh Dr. Van Royen, sedangkan Ells-worth Bunker dari AS berperan aktif menjadi perantaranya. Persetujuan New York tanggal 15 Agustus 1962 berisi penyerahan Papua bagian barat dari Belanda kepada Indonesia melalui United Nations Tempo-rary Executive Authority (UNTEA). Berikutnya, pada tanggal 1 Mei 1963 bendera Merah Putih berkibar di Irian Barat. Kedudukan Irian Barat di mata internasional menjadi makin kuat setelah diadakan Penen-tuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969, di mana rakyat Irian Barat memilih tetap bersatu dalam NKRI.
139
bab5-6 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 139 7/10/12 2:16 PM

Keinginan tersebut tidak sesuai dengan Persetujuan Manila54 sehingga ditentang oleh Presiden Soekarno yang menganggap pembentukan Federasi Malaysia yang sekarang dikenal sebagai Malaysia sebagai “boneka Inggris“. Federasi Malaysia dinilai sebagai cara-cara kolonialisme dan imperialisme dalam bentuk baru serta dukungan terhadap berbagai gangguan keamanan dalam negeri dan pemberontakan di Indonesia. Bahkan ketika PBB menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap, Presiden Soekarno menarik Indonesia dari PBB pada tanggal 20 Januari 1965 dan membentuk Conference of New Emerging Forces (Conefo). Meskipun konfrontasi “terhenti” karena G-30S/PKI tetapi Malaysia sebagai salah satu Negara Persemakmuran telah memiliki aliansi pertahanan dengan Inggris, Australia, Singapura, dan Selandia Baru yang tergabung ke dalam Five Power Defense Arrangement (FPDA) yang dibentuk pada tahun 1971. Aliansi tersebut sengaja dibentuk untuk membendung pengaruh Indonesia dan kemungkinan agresinya. Salah satu kesepakatan negara-negara FPDA adalah klausul bahwa serangan terhadap salah satu negara anggota merupakan serangan pula terhadap negara anggota lainnya. Saat peringatan 30 tahun FPDA pada November 2001, kelima negara anggotanya sepakat membentuk suatu kerjasama jangka panjang. Periode ini juga menandai berakhirnya hubungan Indonesia dengan Rusia dan Cina karena ancaman komunisme. Peluang ini dimanfaatkan oleh “pihak Barat” untuk kembali merajut hubungan baik termasuk pada bidang pertahanan dan keamanan.
Periode 1966-1999. Meskipun masih tergabung ke dalam GNB, tampak pemerintah Orde Baru lebih condong untuk menjalin hubungan baik dengan AS dan negara-negara blok Barat. AS sangat berkepentingan menanamkan pengaruhnya di Asia Tenggara untuk mencegah gelombang pengaruh komunisme dari Vietnam. Dukungan AS sangat kuat, bahkan
54 Persetujuan Manila berasal dari inisiatif Presiden Filipina Diosdado Macapagal yang sebenarnya ditujukan untuk meredakan ketegangan antara Indonesia dengan Federasi Malaya. Ketegangan mencuat setelah hasil jajak pendapat rakyat Sabah di Kalimantan sebelah utara, Brunei dan Sarawak (Report of the Commission of the Inquiry North Borneo pimpinan Lord Cabbold dari Inggris), terpecah dan tidak sepenuhnya bersedia tergabung dengan Federasi Malaysia yang ingin dibentuk. Persetujuan tersebut ditanda-tangani pada tanggal 31 Juli 1963 oleh kepala-kepala pemerintahan ketiga negara yang intinya sepakat bahwa penyelidikan kehendak rakyat di wilayah tersebut harus dilakukan oleh PBB sebelum pembentukan Federasi Malaysia. Tetapi Perdana Menteri Tengku Abdul Rachman menyatakan pembentukan Federasi Malaysia sebelum misi PBB menyampaikan laporan hasil peninjauannya. Bahkan Sekjen PBB U Thant pun menyesalkan tindakan pemerintah Inggris yang kurang mendukung misi PBB tersebut. Presiden Soekarno memutuskan hubungan diplomatik pada tanggal 17 September 1963, dan menyatakan dukungannya terhadap pejuang-pejuang kemerdekaan di Kalimantan sebelah utara yang dipimpin oleh Azahari.
140
bab5-6 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 140 7/10/12 2:16 PM

ketika Indonesia memutuskan untuk menggabungkan Timor Timur sebagai provinsi ke-30. AS mencabut penangguhan bantuan militer pada 1967 dan memulai kembali dukungannya terhadap militer Indonesia, berupa latihan-latihan dan pengadaan persenjataan ringan.
Pembentukan ASEAN pada tahun 1967 menunjukkan keinginan Indonesia untuk lebih merangkul negara-negara tetangga dan mengurangi ketegangan dan/atau konflik. ASEAN memainkan peranan penting untuk menjaga stabilitas keamanan di kawasan sehingga Indonesia dapat lebih berkonsentrasi kepada pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Berbagai gangguan keamanan dalam negeri berhasil di atasi dengan cepat meskipun penanganan separatisme di Aceh dan Papua kurang mendapat perhatian yang proporsional sehingga strategi yang diterapkan pun kurang tepat. Pembelian persenjataan besar-besaran dari negara-negara Barat di awal 1980-an sangat mempengaruhi konstelasi militer di kawasan. Gelombang pengadaan persenjataan berikutnya dilakukan di pertengahan tahun-tahun 1990-an meskipun kondisi material yang dibeli tidak sepenuhnya baru 100 %.
Krisis Moneter tahun 1997 mengakibatkan kondisi Sospol yang kurang menguntungkan sehingga memaksa aksi unjuk rasa menuntut reformasi di segala bidang kehidupan. Hubungan dengan “pihak Barat” kembali merenggang karena isu-isu pelanggaran HAM dan kebebasan bagi masyarakat untuk menuntut hak-hak politiknya. Kondisi tersebut semakin meruncing hingga Mei 1998 dan referendum untuk Timor Timur pada Agustus 1999, yang didukung oleh pihak yang semula mendukung integrasi, yakni AS dan sekutunya. Pada Oktober 1999, PBB membentuk UNTAET untuk bertanggung jawab selama masa transisi. Resolusi DK PBB juga mengijinkan INTERFET pimpinan Australia untuk memaksa masuk dan berhadapan langsung dengan kekuatan TNI. Keputusan Presiden Habibie akhirnya mengakhiri kemungkinan adanya perang terbuka antara Indonesia dan Australia. Terkait situasi pada saat itu, Presiden SBY pernah menyatakan bahwa hasil jajak pendapat di Timor Timur pada tahun 1999 merupakan buah dari reformasi di Indonesia. Sebagaimana negara Indonesia mengakui Timor Leste yang merdeka, MPR saat itu pada tahun 1999 juga mengakui hasil jajak pendapat tersebut.
Periode 1999-2011. Meskipun memasuki masa-masa sulit, Indonesia akhirnya berhasil menyelesaikan beberapa agenda Reformasi. Setelah krisis keuangan mereda, penyelesaian masalah pertahanan dan keamanan dapat lebih dikonsentrasikan. Perlahan-lahan hubungan baik
141
bab5-6 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 141 7/10/12 2:16 PM

dengan pihak Barat menghangat seiring pencabutan embargo militer dari AS dan sekutunya pada tanggal 22 November 2005. Normalisasi hubungan militer dengan Indonesia, termasuk melanjutkan program Pendidikan dan Pelatihan Militer Internasional (IMET) dan penjualan peralatan militer non-lethal disampaikan menindaklanjuti pernyataan Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice, yang juga disampaikan oleh Presiden George W. Bush saat bertemu Presiden SBY di sela-sela pertemuan APEC di Busan, Korea Selatan. Hubungan baik juga terjalin dengan Rusia dan Cina. Masalah di eks Timor Timur dapat diselesaikan secara permanen.
Pemerintah RI dan Pemerintah Timor Leste telah membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) RI-Timor Leste pada tanggal 14 Desember 2004 guna menangani masalah akuntabilitas terkait dengan peristiwa di Timor Timur tahun 1999. KKP adalah mekanisme bilateral yang belum pernah ada dan pertama di dunia dengan tujuan untuk menetapkan kebenaran akhir peristiwa di Timor Timur tahun 1999 dan menutup kasus-kasus terkait berdasarkan prinsip rekonsiliatif dan berwawasan ke depan.
Separatisme GAM juga diselesaikan dengan mekanisme negosiasi melalui diplomasi publik sehingga diakui oleh dunia internasional sebagai keberhasilan diplomasi pemerintahan Presiden SBY. Perundingan RI-GAM berlangsung sebanyak 5 putaran dengan melibatkan Crisis Management Initiative (CMI), The Henry Dunant Center dan mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari sebagai mediator. Penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah RI dan GAM, akhirnya dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2005 untuk mengakhiri konflik yang berlangsung di Aceh selama ini.
Pada sisi lain, pemerintah juga menghadapi sengketa Ambalat. Kekalahan Indonesia di Mahkamah Internasional atas kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan tahun 2002 ternyata berlanjut dengan klaim Malaysia atas perairan Ambalat di Kalimantan Timur. Pada tanggal 16 Februari 2005, Malaysia memberi konsesi penambangan minyak di Blok Ambalat kepada Royal Dutch Shell dan Petronas padahal Indonesia jauh sebelumnya sudah melakukan aktivitas di Ambalat dengan izin eksplorasi minyak dan gas kepada ENI (Italia) dan Unocal (AS). Kapal-kapal perang TNI AL segera berdatangan di perairan tersebut dan sudah beberapa kali terjadi insiden yang memaksa pemerintah kedua negara untuk berunding. Selain Ambalat, maka Indonesia juga harus mencermati potensi konflik di Laut Cina Selatan. Meskipun Indonesia bukan merupakan penuntut atas gugus Kepulauan Spratly, akan tetapi Indonesia memiliki fakta sengketa bilateral dengan Cina atas
142
bab5-6 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 142 7/10/12 2:16 PM

landas kontinen di sepanjang kawasan Laut Cina Selatan. Hal ini tidak mencuat ke permukaan mengingat RRC masih tetap meyakinkan Indonesia bahwa tidak ada masalah perbatasan maritim dengan Indonesia di Laut Cina Selatan. Padahal berdasarkan peta RRC pada tahun 1947 yang menunjukkan sembilan garis putus-putus dan berbentuk lidah tersebut meliputi wilayah Pulau Hainan sampai ke pantai Kalimantan yang mencakup Teluk Tonkin, Kepulauan Paracel dan Kepulauan Spratly. Demikian pula pada tahun 1995, berdasarkan peta RRC menunjukkan bahwa ladang gas Natuna berada dalam teritorialnya, walaupun terletak lebih dari 1.000 NM sebelah selatan RRC. Selain itu Cina juga pernah menyatakan klaim terhadap sebagian Laut Natuna sampai ke perairan Pulau Bangka dan 20 NM dari Kalimantan Barat dan sekeliling Vietnam. Selain beberapa kali terjadi insiden dengan kapal perang Vietnam, Cina juga sudah berulang kali menggelar latihan perang di perairan Laut Cina Selatan.
Konteks Strategis Perkembangan Militer IndonesiaDalam proses perkembangan militer Indonesia yang telah dijelaskan di atas ada beberapa hal yang bisa diangkat sebagai konteks yang melatari bagaimana perkembangan itu bisa berlangsung. Tentu saja terdapat karakteristik yang berbeda di setiap kurun waktu. Namun demikian, beberapa hal pokok yang bisa dijadikan sebagai konteks umum dari perkembangan itu di antaranya adalah, pertama, faktor politik. Partai-partai politik berlomba terutama kelompok sosialis/komunis berusaha sekuat tenaga untuk menguasai Angkatan Perang, sehingga TNI dan PPAL adalah hasil kompromi politik (masa 1960-an). Kedua, faktor kepemimpinan. BKR, TKR, TRI, TNI dan Laskar adalah tentara revolusi yang lahir dari kebangkitan massa rakyat karena panggilan suci untuk mempertahankan kemerdekaan. Gagasan yang lahir dari pikiran pemimpin tertinggi militer, mejadi landasan dari proses perubahan di setiap periode kepemimpinan. Ketiga, faktor diplomasi. Perkembangan diplomasi dan reaksi terhadap pembangunan kekuatan lawan juga mempengaruhi perubahan dan perkembangan organisasi TNI. Keempat, faktor strategi perjuangan. Adanya perbedaan strategi perjuangan antara tokoh-tokoh politik dan militer. Kelima, faktor reorganisasi dan rasionalisasi. Setelah adanya Reorganisasi dan Rasionalisasi TNI 1948, organisasi TNI tersusun berdasarkan satu strategi yaitu Atrition Strategy, di mana organisasi, dislokasi, kategorisasi disusun berdasarkan acuan strategi untuk siap melakukan perang jangka panjang.
143
bab5-6 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 143 7/10/12 2:16 PM

5.3. Dampak Jangka Panjang Perkembangan Militer Indonesia
Perkembangan militer Indonesia yang berangkat dari lingkungan strategis yang terus menerus berubah dalam perjalanannya memberikan dampak yang sampai saat ini masih dirasakan di dalam institusi militer Indonesia, di antaranya, pertama, Organisasi BKR merupakan suatu korps pejuang bersenjata meskipun bukan angkatan bersenjata reguler. Bersama KNI, BKR menjadi organisasi-organisasi rakyat yang tidak sekedar bertugas membantu, melainkan untuk mendorong dan memimpin perjuangan. Kekuasaan dipegang oleh KNI dan BKR, di awal proklamasi mereka mengisi jabatan-jabatan, menyusun alat-alat negara dan memutar roda revolusi; kedua, bulan Oktober 1945 pemerintah memanggil Oerip Soemohardjo ke Jakarta untuk diserahi tugas menyusun organisasi tentara. Organisasi TKR pada awalnya (1945) disusun model organisasi KNIL dan Departemen Peperangan (Departement Orlog/DVO) Hindia Belanda. Hanya tidak mempunyai inspektorat-inspektorat kesenjataan infanteri, artileri dan kaveleri. Pada mulanya direncanakan untuk membentuk empat divisi yaitu tiga di Jawa dan satu di Sumatera. Namun tidak dapat direalisasikan karena kenyataannya baik di Jawa maupun di Sumatera jumlah pemuda yang memasuki TKR melebihi dari jumlah yang diperlukan. Dan pembentukan kesatuan-kesatuan tersebut dilakukan secara spontan mulai dari bawah di tengah-tengah kancah perjuangan. Oleh sebab itu, Kepala Staf Umum terpaksa mengesahkan terbentuknya sepuluh divisi di Jawa dan enam divisi di Sumatera; ketiga, pada masa Kabinet Syahrir Pertama, Markas Tertinggi dipecah menjadi Markas Besar Tentara (MBT) dan Direktorat Jenderal Militer. MBT berada di bawah Jenderal Soedirman, sedangkan Dirjen Militer di bawah Jenderal Mayor Soedibyo; keempat, perubahan dari Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat dan menjadi TRI pada tanggal 24 Januari 1946 membawa konsekuensi dilakukan penyempurnaan organisasi dengan ditetapkannya formasi dan susunan Markas Besar dan Kementerian Pertahanan, Soedirman dan Oerip Soemohardjo tetap menduduki jabatan semula masing-masing sebagai Panglima Besar dan Kepala Markas Besar Umum. Di Kementerian Pertahanan dibentuk beberapa bagian seperti Direktorat Jenderal, Kepala Personalia, dan Kepala Kehakiman, dan lain-lain; kelima, selesai penyempurnaan organisasi dilakukan pemilihan-pemilihan panglima divisi yang ternyata tidak selalu diterima di daerah. Di tingkat jawatan-jawatan dalam lingkungan Kementerian Pertahanan juga timbul kesulitan-kesulitan sehingga muncul
144
bab5-6 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 144 7/10/12 2:16 PM

adanya dua sistem komando yaitu yang pertama langsung dari Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin dan yang satu lagi dari Panglima Besar Jenderal Soedirman, dan ini tidak menguntungkan semangat perjuangan pada saat itu. Di Kementerian Pertahanan dibentuk pula Biro Perjuangan, Koordinator laskar-laskar atau Badan Perjuangan di bawah Djoko Suyono; keenam, sejak 3 Juni 1947 disahkan berdirinya TNI sebagai tindak lanjut peleburan TRI dan Laskar dengan model kepemimpinan kolektif dalam bentuk pucuk pimpinan TNI. Ketua pucuk pimpinan TNI Jenderal Soedirman, dengan 3 orang dari unsur TRI (Oerip, M. Nasir, dan Suryadarma) dan 3 orang dari unsur laskar (Sumarsono, Sutomo, dan Ir. Sakirman).
Akibat peleburan tersebut, organisasi TNI menggelembung, bukan organisasi militer yang ideal; ketujuh, pada TNI AL terdapat sumber dari laskar yaitu Marine Keamanan Rakyat yang dipimpin oleh Atmadji berpangkat Laksamana yang membawahi divisi-divisi Tentara Laut Republik Indonesia (TLRI) yang berideologi kiri (komunis). Di Yogyakarta telah dibentuk Markas Tertinggi AL di bawah Laksamana M. Pardi. Dualisme organisasi AL diselesaikan pada bulan Februari 1946, di bawah pimpinan Jenderal Soedirman, Angkatan Laut menerima nama resmi ALRI. Pada bulan Juli 1947, dalam tubuh ALRI dibentuk kepemimpinan kolektif Pucuk Pimpinan Angkatan Laut (PPAL) untuk menyelesaikan dualisme kepemimpinan; kedelapan, pada TNI AU pengaruh perubahan organisasi sejalan dengan ditingkatkannya BKR menjadi TKR sejak 5 Oktober 1945. BKR Udara otomatis menjadi TKR Udara yang dikenal dengan TKR Jawatan Penerbangan. Pembentukan kekuatan udara dimulai dari inisiatif Markas Tertinggi TKR; kesembilan, pelopor dan pendukung BKR Udara/TKR Jawatan Penerbangan kebanyakan bekas anggota-anggota penerbangan Belanda dan juga bekas anggota penerbangan Jepang di samping para pemuda pejuang lainnya, sehingga unsur profesionalisme lebih dominan. Dalam waktu relatif singkat TKR Jawatan Penerbangan semakin meningkat kemajuan yang dicapai setelah Suryadarma memegang tampuk pimpinan TKR Jawatan Penerbangan. Aktivitas semakin meningkat dan struktur organisasi semakin teratur. Perkembangan organisasi TNI AU sejalan dengan pengaruh perkembangan organisasi TNI. Sesuai dengan lahirnya embrio TNI yakni dimulai dari BKR dan berlanjut TKR, TRI, TNI, ABRI dan kembali menjadi TNI.
Dalam konteks ini, sengaja tidak dibeberkan secara panjang lebar dan rinci bagaimana perubahan itu dilakukan dan dikelola karena titik tolak dalam analisis buku ini adalah pada bagaimana perubahan institusional itu sesungguhnya berlangsung sebagai akibat perubahan yang lebih luas di dalam lingkup strategis TNI itu sendiri yang kemudian berpengaruh pada postur TNI sepanjang periode 1945 sampai dengan hari ini.
145
bab5-6 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 145 7/10/12 2:16 PM

5.4.
Rangkuman
Sepanjang perjalanan perkembangan TNI, kiranya bukti bahwa proses perubahan itu berlangsung tentu tidak bisa diingkari, meskipun sejauh mana perubahan itu berdampak bagi peningkatan kapasitas struktural TNI dan sejauh mana perubahan itu adalah hasil dorongan dari apa yang diidentifikasi sebagai potensi ancaman dan tantangan nasional yang bersumber dari dinamika ekonomi politik global belum bisa dipastikan secara jelas. Begitu juga sebaliknya, dalam beberapa kesempatan, sejauh mana TNI bisa memberikan sumbangsih bagi terciptanya norma-norma baru dalam tata hubungan militer antar negara di dunia belum bisa dijelaskan secara lebih detail. Namun demikian, kenyataan bahwa perubahan itu berlangsung dan terjadi dalam skala kualitatif tertentu bisa menjadi dasar pijakan bagi proses merancang transformasi selanjutnya.
Reorganisasi dan restrukturisasi TNI yang dijalankan dalam beberapa periode waktu, menunjukkan betapa selama masa-masa awal berdirinya, TNI jauh lebih disibukkan oleh persoalan internal, baik internal di dalam tubuh TNI maupun internal yang sifatnya persoalan politik dalam negeri. Dinamika politik dalam negeri pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno sampai dengan tahun 1966 menjadi faktor pendorong yang cukup kuat bagi TNI untuk beradaptasi dengan situasi yang berlangsung. Relasi politik yang cukup kuat semasa periode ini telah membuat dinamika perubahan organisasional TNI begitu cepat. Kendati begitu, dari sudut pandang yang agak berbeda, kiranya kita bisa melihat bahwa pada masa tersebut adalah masa di mana TNI sedang berbenah untuk mencari format kelembagaan yang ideal. Kenyataan bahwa TNI dibentuk oleh satuan-satuan perang resmi dan laskar-laskar mandiri yang dimiliki oleh rakyat menjadi persoalan pokok yang harus dipecahkan pada periode tersebut. Tetapi, apakah posisi ini hanya bisa dilihat secara satu arah, yakni TNI menjadi obyek dari proses politik dalam negeri yang begitu dinamis. Hal ini bisa kita lihat lebih dalam dengan menganalisis bagaimana agen-agen di dalam tubuh TNI juga secara praktis memainkan peran di dalam institusi-institusi politik yang ada, baik secara institusional maupun personal. Dan dalam beberapa hal, kapasitas individu di dalam tubuh institusi TNI pada prosesnya membuktikan bahwa TNI secara kelembagaan adalah salah satu institusi yang bisa secara efektif melahirkan generasi kepemimpinan yang handal. Kondisi tersebut telah berlangsung hingga kini, terutama pasca tumbangnya rezim pemerintahan Presiden Soekarno yang
146
bab5-6 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 146 7/10/12 2:16 PM

kemudian digantikan oleh Orde Baru di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto. Setelah periode ini, TNI semakin bisa mengukuhkan diri sebagai institusi yang bisa secara efektif melahirkan kepemimpinan baru.
Sejak awal kemerdekaan, Indonesia telah sedemikian terhubung dengan persoalan-persoalan global, bahkan sampai hari ini. Demikian juga dengan TNI sebagai institusi militer Indonesia yang secara historis sangat terkait erat dengan sistem pendidikan militer yang diajarkan oleh Jepang (PETA) dan Belanda (KNIL). Meskipun ada kelompok laskar rakyat, namun dalam perkembangannya kelompok laskar rakyat yang tidak mendapat pendidikan militer secara khusus, pada akhirnya harus “tersingkir”, terutama karena pada pucuk pimpinan TNI hanya dipegang oleh dua kelompok perwira dari latar pendidikan militer yang telah mapan. Ketegangan yang muncul di antara dua kelompok perwira itu juga pada proses perkembangan TNI cukup mewarnai dinamika internal institusi. Dari penjelasan itu, kita bisa langsung melihat bahwa dari semenjak kelahirannya, TNI sesungguhnya terkait erat dengan nilai-nilai dan norma-norma yang dibangun oleh kekuatan tentara dari Jepang dan Belanda. Secara teoritis, nilai-nilai ini berpeluang direproduksi oleh anggota TNI saat ini dan ke depan dalam kualitas dan konteks yang berbeda.
Selanjutnya, dalam perkembangan TNI, terutama ketika periode Perang Dingin, tarik ulur antara kepentingan AS dan Uni Sovyet secara kasat mata dapat kita lihat dengan agenda-agenda strategis yang digulirkan oleh TNI, terutama terkait dengan pengembangan sistem persenjataan pertahanan nasional dan peningkatan kapasitas prajuritnya. Perkembangan Alutsista yang memadai pada era Perang Dingin adalah isu sentral, karena terkait dari mana senjata itu akan didatangkan karena hal ini selanjutnya akan membuktikan pada dunia internasional di mana posisi Indonesia dalam pertarungan antara AS dan Uni Sovyet. Demikian juga dengan pengiriman prajurit untuk sekolah dan belajar strategi perang, pada saat itu, hanya ada dua pilihan, berangkat ke AS atau Uni Sovyet atau ke negara anggota blok Barat maupun blok Timur. Seperti halnya senjata, harus didatangkan dari AS ataupun Uni Sovyet. Problem dualisme kepemimpinan dunia ini justru dijawab Indonesia dengan satu gagasan yang belum pernah terpikirkan sebelumnya, mendirikan GNB.
Sebagai salah satu negara yang mempelopori GNB, Indonesia tentu saja mencoba memainkan peran lebih strategis dengan menghimpun negara-negara yang baru merdeka untuk terlepas dari pertikaian besar dunia dengan membangun
147
bab5-6 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 147 7/10/12 2:16 PM

satu paradigma politik luar negeri yang sebelumnya tidak terpikirkan, yakni politik luar negeri bebas aktif, yang tidak berpihak pada salah satu blok besar dunia. Kendati prinsip ini dalam perjalanannya terbukti tidak mudah, tetapi inisiatif terobosan yang visioner ini membuktikan bahwa Indonesia sebagai sebuah negara memiliki kemampuan untuk memasukkan satu nilai baru yang bertentangan dengan pandangan umum saat itu. Kendati secara ekonomi Indonesia masih terseok-seok dan secara politik baru saja mendapat pengakuan kemerdekaan dari beberapa gelintir negara anggota PBB ditambah dengan pemberontakan-pemberontakan di dalam negeri, tetapi kenyataan tersebut membuktikan bahwa Indonesia tidak saja bertindak selaku agen yang di-drive oleh satu struktur yang demikian menentukan setiap keputusan negara-negara di dunia, namun juga sebagai subyek, Indonesia bisa membuat satu terobosan yang menjadi landasan bagi bentuk-bentuk interaksi negara-negara di dunia pada masa depan. Gagasan yang baik itu, walaupun tidak mampu menghentikan Perang Dingin atau fakta bahwa pada akhirnya GNB harus pecah karena Perang Arab, tidak lantas mengecilkan peran Indonesia dalam kancah hubungan internasional.
Kedua penjelasan di atas kiranya bisa membuktikan satu tesis Giddens yang melihat bahwa dalam proses strukturasi yang diwarnai oleh apa yang dinamakan dengan keterbatasan struktural (structural constraint), agensi masih sangat berperan dalam memberikan warna pada bentuk-bentuk strukturasi yang memungkinkan menstrukturkan struktur itu sendiri. Bahwa Indonesia seperti halnya negara-negara yang baru merdeka di akhir Perang Dunia Kedua serta pada masa Perang Dingin secara relatif nampak tersubordinasi oleh kekuatan besar dunia, namun upaya Indonesia untuk bisa memainkan peranan di kancah internasional – apapun hasil akhirnya – pada prosesnya terjadi, berlangsung dan memberikan dampak dalam skala tertentu. Secara sosiologis tentu saja apa yang dilakukan oleh Indonesia pada masa itu bisa dilihat sebagai tindakan agen negara dalam satu proses interaksi sosial yang mengarah pada satu bentuk upaya mempengaruhi struktur kekuatan dunia yang didalamnya tidak saja diwarnai oleh bentuk-bentuk konflik dan ketegangan melainkan juga ada kejadian-kejadian yang sifatnya negosiatif antara negara-negara yang memiliki kekuasaan besar dengan Indonesia.
148
bab5-6 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 148 7/10/12 2:16 PM

149
Tabel 7. Peta Dinamika Internal TNI dan Konteks Strategis dari Masa ke Masa
bab5-6 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 149 7/11/12 1:43 PM

150
bab5-6 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 150 7/11/12 1:43 PM

151
Diolah dari berbagai sumber
bab5-6 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 151 7/11/12 1:43 PM

152
bab5-6 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 152 7/10/12 2:16 PM

Bab VI
Skenario Awal Transformasi TNI• Mengapa Perlu Transformasi?• Skenario Tingkat Global• Skenario Tingkat Nasional• Rangkuman
153
bab5-6 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 153 7/10/12 2:16 PM

Bab VI
Skenario Awal Transformasi TNIKemampuan suatu komunitas dalam menangkap gejala-gejala perubahanlah yang menentukan sejauh mana ia akan dapat mengambil manfaat dari proses perubahan itu sendiri. Demikian kiranya benang merah yang dapat kita tarik dari rangkaian penjelasan yang telah dijabarkan sebelumnya. Pada bagian awal kita telah bahas secara mendetail pandangan-pandangan teoritis dan perspektif pemikiran mengenai globalisasi dari berbagai kalangan. Secara ringkas, dari pemahaman-pemahaman yang diuraikan itu, kita layak menyatakan bahwa globalisasi dengan segala macam dinamikanya adalah satu gejala akhir dari proses modernisasi itu sendiri (late modernity). Meskipun ia memiliki kemampuan untuk mendorong tindakan-tindakan para aktor yang terlibat dalam hubungan-hubungan sosial yang rumit tapi tetap memungkinkan para aktor untuk bisa eksis sebagai dirinya sehingga dalam beberapa hal kemampuan dan kapabilitas para aktor ini bisa sangat menentukan ke mana norma-norma global itu akan bergerak untuk kemudian kembali melintasi ruang dan waktu untuk bersinggungan dengan para aktor itu kembali. Memang betul, globalisasi itu seringkali melahirkan kejutan-kejutan baru tak terduga (unexpected emergence), atau bisa juga dikatakan mengandung banyak ketidakpastian (uncertainties) yang bisa merubah pola pikir dan perilaku masyarakat di dunia. Dengan prinsip-prinsip seperti itulah risiko-risiko dari globalisasi itu layak dipertimbangkan oleh para aktor yang terlibat di dalamnya.
6.1.
Mengapa Perlu Transformasi?
Jelas pertanyaan ini tidak akan mudah. Akan tetapi diskusi mengenai persoalan keamanan nasional mengerucut pada satu pemahaman yaitu arah perkembangan institusi militer nasional suatu negara akan ditentukan oleh kebijakan otoritas negara dalam mendefinisikan persoalan keamanan nasionalnya. Dengan memperhitungkan aspek-aspek tantangan dan ancaman yang muncul dalam persoalan keamanan nasional mereka, arah pergerakan dari institusi militernya bisa dicermati dan diantisipasi.
Penjelasan mengenai perubahan cara pandang yang berhubungan dengan persoalan keamanan semakin perlu untuk dikaji lebih lanjut dengan munculnya varian-varian
154
bab5-6 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 154 7/10/12 2:16 PM

baru konsep keamanan seperti, keamanan lingkungan, keamanan kemanusiaan dan keamanan ekonomi. Jika dianalisis lebih mendalam, keberadaan aktor-aktor negara ternyata tetap menjadi kunci pokok bagaimana kondisi keamanan itu bisa diadakan dan dijaga kualitasnya. Meskipun konsepsi keamanan varian baru tersebut dalam beberapa hal seperti melemahkan batas-batas dan otoritas kewenangan dari negara, tetapi sekali lagi, justru di tengah perdebatan yang berjalan, negara selalu menjadi entitas yang senantiasa terpacu untuk terlibat secara aktif dalam setiap proses penciptaan keamanan-keamanan jenis ini.
Dalam praktiknya, tumbuhnya industri keamanan swasta yang dalam beberapa hal seolah menggantikan peran negara dalam menciptakan situasi aman yang dimaksud tidak akan pernah bisa berkembang sampai taraf yang begitu memukau tanpa ada keterlibatan negara dengan kebijakannya. Justru keterlibatan dan kebijakan negaralah yang memungkinkan ruang manuver industri keamanan swasta itu menjadi semakin lebar. Asumsi bahwa mekanisme pasar bisa diciptakan tanpa adanya campur tangan dari negara pada dasarnya justru salah, karena pasar hanya bisa bertahan dan terus bertahan untuk hidup jika, dan hanya jika, mereka menggantungkan diri pada entitas yang bernama negara. Kasus paling baru dari fenomena ini tentu saja bisa kita saksikan di Eropa dan AS. Tanah di mana kapitalisme itu dilahirkan, pada kenyataannya kembali mengubur kembali kapitalisme sampai pada satu titik di mana pada akhirnya negaralah yang harus turun tangan mengatasi akibat nyata dari bobroknya sistem kapitalisme. Dengan kata lain, ketika kita berbicara perihal persoalan keamanan, tentu saja, diskursus yang terjadi pada level internasional maupun regional tidak lain hanya bisa kita lihat sebagai satu arena di mana yang namanya kepentingan nasional itu dikontestasikan atau disandingkan tetapi bukan dileburkan. Ketika kesepakatan-kesepakatan internasional maupun regional mengenai kerjasama-kerjasama keamanan dilakukan, hal itu bukanlah representasi dari peleburan maupun pencampuran kepentingan nasional pihak yang bersepakat, melainkan persandingan masing-masing kepentingan nasional dalam kualitas yang tentu saja bisa dirundingkan. Karena inti dari perjanjian kerjasama tersebut tidak lain adalah demi masuknya kepentingan nasional dalam mufakat internasional maupun regional. Bahwasanya ketika kesepakatan itu telah disetujui, kemudian norma-normanya bersifat memaksa semua pihak untuk tunduk dan patuh atas kesepakatan yang dimaksud, ini tidak bisa dilihat secara satu arah. Dan bahwa norma global itu mempengaruhi keputusan nasional mereka, juga belum tentu selalu terjadi, melainkan harus juga dilihat sifat resiprositas dari munculnya norma-norma tersebut.
155
bab5-6 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 155 7/10/12 2:16 PM

Terkait dengan persoalan transformasi militer yang dilakukan oleh negara-negara di dunia, kiranya kita bisa saksikan bagaimana dalam waktu yang relatif pendek (sejak peperangan generasi ketiga sampai kelima) perubahan mendasar dari konsep mengenai perang dan/atau peperangan itu berlangsung begitu cepat dan massif. Perubahan ini selain didorong oleh adanya norma-norma global mengenai perang yang mengikat, juga terjadi akibat modernisasi dan industrialisasi teknologi peralatan perang di berbagai negara. Transformasi militer yang dalam banyak hal sering diasosiasikan dengan Revolutionary in Military Affairs ataupun Military Technical Revolution mengandung kesempatan sekaligus ancaman tersendiri bagi negara. Barangkali memang begitulah setiap nilai global yang muncul dan ditawarkan kepada masyarakat, seperti halnya mata pisau, ada yang tumpul dan yang tajam, atau dalam bahasa yang ringkas, ia mengandung risiko, yakni risiko global itu sendiri.
Perkembangan teknologi perang yang cukup massif mendorong setiap negara untuk lebih efisien dalam membangun angkatan perang mereka. Namun demikian, kemajuan teknologi yang dipelopori oleh Barat mengakibatkan rawan ketergantungan produksi senjata dari negara-negara berkembang. Apa yang dilakukan Cina dengan membangun industri persenjataan nasional bisa menjadi contoh bagaimana proses transformasi militer juga bisa memicu pertumbuhan ekonomi nasionalnya. Terlepas dari kontroversi mengenai kualitas dari produk yang diciptakan, Cina telah menunjukkan bagaimana kemajuan teknologi juga bisa dicapai oleh siapa saja, tak terkecuali negara-negara berkembang. Kendati begitu, bukan tidak mungkin ketika Cina mengalami kelebihan produksi teknologi perangnya, mereka juga akan membutuhkan negara-negara baru sebagai pasar. Di sini, meskipun Cina adalah kelompok negara berkembang yang di dalam setiap forum-forum internasional seolah bersuara mewakili negara berkembang, namun kepentingan nasional mereka jelas lebih dikedepankan daripada apapun. Artinya, ancaman munculnya ketergantungan nasional atas jenis persenjataan baru kembali terbuka.
Fakta lain mengenai revolusi dalam peralatan perang yang secara sosiologis menarik untuk dicermati adalah bagaimana teknologi-teknologi yang diciptakan oleh dunia Barat yang mereka klaim sebagai demi kepentingan nasional mereka, pada prosesnya telah memperkuat berbagai macam perlawanan terhadap supremasi Barat itu sendiri. Seperti kapitalisme yang lahir dan “sekarat” di dunia Barat, begitu pula dengan persenjataan yang mereka produksi telah memperkuat basis militer kelompok-kelompok yang secara idiologis bertentangan dengan mereka. Apa yang terjadi di
156
bab5-6 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 156 7/10/12 2:16 PM

Afghanistan, Pakistan, Irak dan negara-negara lainnya menunjukkan bahwa perlawanan terhadap dunia Barat dilengkapi dengan persenjataan yang diproduksi oleh negara-negara Barat itu sendiri. Demikian juga dengan bentuk-bentuk kejahatan transnasional yang baru seperti terorisme maupun perompakan di tengah laut, seperti di kawasan perairan Somalia, justru senjata-senjata yang diproduksi oleh industri militer negara-negara Baratlah yang pada gilirannya memperkuat tekanan mereka terhadap keamanan dunia. Sekali lagi inilah paradoks dari perkembangan masyarakat global.
Terkait dengan pembahasan di atas, pertanyaan lanjutan yang layak untuk diajukan dalam konteks kekinian adalah sejauh mana perdebatan itu bisa berkontribusi bagi Indonesia sebagai sebuah negara, dan institusi militernya sendiri dalam melihat globalisasi, keamanan nasional dan transformasi militernya. Di bawah ini akan dicoba untuk dijabarkan bagaimana Indonesia layaknya memandang dinamika ekonomi politik internasional yang berlangsung sekarang pada dua level strategis, baik pada level global maupun level negara.
6.2.
Skenario Tingkat Global
Seperti telah disinggung pada bagian terdahulu, perkembangan dinamika global saat ini menunjukkan kecenderungan yang sangat ketat. Jika semula AS adalah satu-satunya pihak yang paling berkuasa di dunia setelah runtuhnya Uni Sovyet, saat ini kondisinya telah berbeda 180 derajat. AS telah masuk dalam jerat krisis ekonomi yang begitu dalam bahkan perkembangan yang terakhir menunjukkan bagaimana masyarakat AS menyalahkan kapitalisme yang telah “menyengsarakan” mereka. Meski belum sampai pada level yang bisa mengganggu keamanan nasional mereka, protes masyarakat dengan aksi menduduki Wall Street menjadi kekhawatiran tersendiri bagi AS yang terancam mengalami krisis multidimensional. Situasi itu sejalan dengan apa yang terjadi di Eropa belakangan ini, setelah krisis Yunani, saat ini krisis juga dihadapi oleh negara-negara besar Eropa seperti Itali, Spanyol bahkan kemungkinan juga Perancis. Sementara itu, apa yang terjadi dengan Cina dan beberapa negara berkembang yang lain menunjukkan bagaimana mereka kini mengalami booming ekonomi yang sebelumnya hanya menjadi monopoli AS dan Barat. Situasi ini jelas berdampak pada perubahan konstelasi dunia sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan pada perimbangan kekuatan global.
157
bab5-6 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 157 7/10/12 2:16 PM

Jika sebelumnya kekuasaan berada mutlak di tangan AS dan Barat, saat ini Cina telah muncul sebagai raksasa dunia baru. Tidak saja dalam urusan ekonomi seperti India, Cina juga memiliki industri persenjataan yang maju dan modern. Meskipun secara kualitas belum dapat bersaing dengan produksi teknologi militer AS dan Barat, perkembangan yang dilakukan oleh Cina menunjukkan bahwa mereka mampu menjawab persoalan ketergantungan teknologi militernya. Dalam perencanaannya, konon mereka bahkan telah menyiapkan konsep perang luar angkasa guna menandingi kemampuan militer AS.
Kendati ada kecenderungan kekuatan dunia akan mengarah pada dua kekuatan besar tersebut, namun kesimpulan untuk mengatakan bahwa dunia akan menuju pada satu bentuk bipolarisasi – terjadinya pengkutuban yang pada gilirannya menarik negara-negara lain untuk bersekutu – seperti pada era Perang Dingin, tentu saja terlalu dini, mengingat beberapa hal di antaranya: pertama, meskipun berpaham komunisme, tetapi Cina jauh lebih moderat ketimbang Rusia dalam hal penanaman modal asing dan investasi. Apa yang dilakukan Cina saat ini bukan membangun satu imperium persekutuan dengan negara-negara yang secara idiologis sehaluan, melainkan justru membangun satu pengaruh yang cukup kuat baik di negara-negara maju seperti AS dan beberapa negara Eropa serta di negara-negara berkembang di Asia maupun di Afrika dan Amerika Latin melalui investasi dan suntikan modal dalam rangka pembangunan nasional negara-negara tersebut atau dalam rangka mengatasi krisis ekonomi yang tengah berlangsung. Upaya ini tentu saja sangat bertolak belakang dengan interaksi politik masa Perang Dingin; kedua, keterbukaan ekonomi yang melanda dunia pada prosesnya juga tidak bisa dihindari oleh Cina, sehingga keterpurukan perekonomian AS, perlahan tapi pasti juga akan mempengaruhi perkembangan perekonomian Cina. Hal ini tentu juga menjadi perhatian tersendiri dari Cina karena seperti halnya globalisasi yang tidak hanya melindas negara-negara di luar Barat, tetapi juga melemahkan masyarakat Barat itu sendiri. Oleh karena itu, Cina berharap agar perekonomian dunia bisa mencapai keseimbangan agar investasi mereka di negara-negara maju tetap bisa aman sehingga merekapun bisa luput dari krisis; ketiga, persoalan lain adalah keberadaan diaspora orang Cina di hampir seluruh negara di dunia yang dalam prosesnya menjadi bagian integratif dari komunitas bangsa di negara itu, bisa dilihat sebagai salah satu faktor yang secara sosiologis sedikit banyak akan menghambat pertikaian lebih lanjut antara AS dan Cina; keempat, dari sisi AS sendiri yang telah memiliki sekutu tradisionil
158
bab5-6 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 158 7/10/12 2:16 PM

cukup lama, dihadapkan pada satu kenyataan bahwa perekonomian mereka – AS dan sekutunya – sedang berada pada situasi depresi yang dalam perkembangannya justru menarik Cina dan beberapa negara berkembang lainnya untuk bisa terlibat membantu memperbaiki kondisi perekonomian mereka, sehingga paling tidak, kalaupun proses polarisasi itu terjadi, masih dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk memperkuat daya magnetik kutub penariknya.
Dalam konteks inilah, Indonesia dapat memainkan peranannya. Beberapa hal yang bisa menjadi skenario pelibatan Indonesia dalam kancah global di antaranya adalah pelibatan Indonesia dalam proses perdamaian dunia, konsekuensi global dalam membagi risiko dan membangun militer Indonesia yang kuat demi tujuan-tujuan damai dan harmoni dunia.
Indonesia dan Perdamaian DuniaBerangkat dari penjelasan yang telah dikemukakan di atas, kita bisa melihat bahwa meskipun globalisasi mendorong negara-negara untuk bisa melakukan proses adaptasi sehingga manfaat dari globalisasi itu bisa dioptimalkan serta ancaman dan tantangan darinya bisa diminimalisir, globalisasi juga membuka kesempatan bagi negara untuk berperan dalam menciptakan norma universal baru. Oleh karena itu, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang semakin hari eksistensinya semakin dipandang oleh negara-negara lain, termasuk AS dan Barat, sudah selayaknya memulai langkah-langkah inisiatif yang bisa mendorong peradaban dunia ke arah yang lebih harmonis. Penekanan terhadap harmonisasi dunia ini, tentu saja didasari oleh adanya satu pemikiran, meskipun konflik dan ketegangan yang ada di dunia ini akan terus berlangung dalam derajat yang beragam serta memiliki dinamika relasi yang cukup ketat, namun menciptakan perdamaian dunia yang aman, tentram dan adil adalah salah satu dari cita-cita dan tujuan dari republik ini didirikan. Oleh sebab itu melakukan beragam inisiatif di level global dan regional dalam rangka menciptakan iklim perdamaian yang lebih mengedepankan dialog dan kerjasama ketimbang pengerahan kekuatan bersenjata menjadi pilihan yang bisa meminimalkan risiko di berbagai pihak.
Kendati demikian, sikap untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih harmonis tidak bisa secara langsung dikatakan sebagai upaya untuk mendeligitimasi kekuatan militer nasional. Ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Percampuran kedua hal ini akan menimbulkan pemaknaan yang ambigu bagi proses perdamaian dan upaya
159
bab5-6 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 159 7/10/12 2:16 PM

menciptakan harmoni di dunia itu sendiri karena perdamaian dan harmoni itu bukanlah sesuatu yang bisa dianggap selalu ada (taken for granted). Perdamaian dunia adalah satu kondisi atau situasi yang sifatnya dinamis karena menyangkut interaksi para aktor yang satu sama lain memiliki kepentingan masing-masing. Dalam perspektif ini pula, perdamaian dunia mestilah juga dilihat sebagai situasi di mana semua pihak berada dalam posisi membagi risiko mereka satu sama lain. Norma-norma universal yang muncul sebagai konsekuensi dari relasi di antara negara-negara di dunia juga mesti dilihat sebagai bentuk kontestasi paling optimal dari kepentingan-kepentingan nasional negara-negara di dunia.
Kondisi harmoni pada akhirnya kita bisa maknai sebagai satu konstruksi sosial yang di dalamnya berisi agen-agen atau aktor-aktor yang satu sama lain saling berinteraksi secara ketat. Oleh karenanya, kondisi damai atau harmoni itu bisa setiap saat berubah manakala ada salah satu pihak atau lebih yang merasakan adanya ketidakadilan dalam proses interaksi yang ada ataupun merasa dirugikan kepentingan nasionalnya. Jika sampai pada satu titik di mana keamanan nasional satu negara merasa terancam akibat kondisi damai yang dimaksud, bukan tidak mungkin disharmoni akan terjadi dan memicu terjadinya konflik bersenjata antar negara. Dalam konteks ini tentu saja, perdamaian dan harmoni sebagai satu konstruksi sosial harus dijaga dalam satu porsi kesetimbangan. Artinya, syarat utama dari bisa berlangsungnya proses perdamaian dan harmoni itu tidak lain adalah kemampuan kita untuk bisa menjaga dan mempertahankannya dengan baik. Pada titik ini, institusi militer menjadi begitu mendasar kebutuhannya bagi keberlangsungan satu proses perdamaian atau situasi yang dikatakan harmonis itu sendiri.
Indonesia Berbagi Risiko GlobalTidak ada satu pihak pun, bahkan mereka yang mengklaim diri sebagai suku
terasing, yang bisa terlepas dari arus besar globalisasi. Karena globalisasi yang bagai juggernaut itu memiliki kekuatan besar yang melibas siapapun tanpa terkecuali, termasuk kelompok yang membidani lahirnya gelombang besar ini (baca: Barat). Globalisasi dengan berbagai macam gejalanya melahirkan beragam konsekuensi, baik yang disengaja atau memang terprediksikan (intended consequences) maupun yang tidak terprediksi atau terlepas begitu saja (unintended consequences). Karena itulah, siapapun yang berhadapan dengan globalisasi, pasti memiliki risiko, baik risiko yang pasti maupun yang tak pasti atau bahkan yang tidak berwujud (absurd) sekalipun.
160
bab5-6 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 160 7/10/12 2:16 PM

Keberadaan risiko yang seringkali tidak terprediksi secara jelas inilah yang harus dipikirkan oleh setiap pihak yang terlibat dalam proses interaksi global itu. Dalam konteks diskursus keamanan, risiko-risiko yang dimaksud tentu bisa dilihat dari semakin besarnya ancaman terhadap kepentingan nasional yang dalam praktiknya seringkali melintasi batas-batas teritorial suatu negara. Kepentingan nasional tidak lagi terjebak pada pemaknaan sempit, hanya berada di dalam satu wilayah kedaulatan, melainkan juga seringkali ia berada di wilayah negara lain, atau bahkan di wilayah tak bertuan. Pada titik ini, kebijakan luar negeri satu negara menentukan sekali bagaimana risiko itu bisa dikelola dan diminimalisir melalui mekanisme pembagian risiko yang adil dan tetap menghargai kedaulatan nasional masing-masing negara yang terlibat dalam satu kesepakatan.
Dalam konteks ini, apa yang dilakukan oleh Indonesia yang belakangan ini oleh dunia dikatakan sebagai salah satu new emerging countries yang cukup diperhitungkan sudah cukup tepat dengan mendudukkan berbagai persoalan-persoalan keamanan nasionalnya pada porsi yang seimbang dengan perkembangan dinamika ekonomi politik global. Keberadaan Indonesia di G-20 menjadi salah satu indikator bagaimana upaya pelibatan diri yang lebih intens dalam kancah kontestasi global itu diterapkan. Sebagai salah satu negara yang mewakili suara negara-negara berkembang lainnya, Indonesia memiliki peluang untuk menyuarakan kepada negara-negara maju agar risiko yang timbul akibat globalisasi yang pada intinya adalah akibat kerakusan kapitalisme Barat itu bisa secara adil dilihat dan dimaknai secara kritis. Meskipun demikian, pada situasi seperti sekarang ini, terminologi membagi risiko seperti apa yang diungkapkan oleh Giddens bisa bermakna ganda, atau rentan menjadi perangkap bagi negara-negara berkembang.
Kondisi ketidakstabilan yang dialami oleh AS dan Eropa tentu saja menimbulkan gejolak ekonomi politik yang cukup kuat di kawasan. Situasi ini tetaplah harus dilihat secara jeli dan kritis, mengingat, kelompok negara-negara maju bisa memasukkan tema berbagi risiko dalam menghadapi persoalan yang sedang diderita. Berbagi risiko pada hari ini bisa didefinisikan secara kontekstual menjadi berbagi risiko krisis yang sedang dialami oleh negara maju. Di sinilah problematika konsepsi berbagi risiko menjadi penting untuk dikembalikan pada kepentingan nasional masing-masing negara. Sehingga berbagai dampak dari proses berbagi risiko krisis tersebut tidak lantas justru kontra produktif bagi perkembangan pembangunan nasional, atau bahkan mengurangi dalam derajat tertentu kepentingan nasional negara-negara berkembang, khususnya Indonesia.
161
bab5-6 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 161 7/10/12 2:16 PM

Namun demikian, mengambil sikap dan berjarak terhadap risiko yang tengah dihadapi oleh AS dan Barat juga bukan satu keputusan yang bijak karena dalam beberapa hal risiko itu sekali lagi tidak bisa dihindari. Secara sederhana kita bisa me-lihat, meskipun saat ini Indonesia menyandarkan pertumbuhan ekonominya pada pasar domestik, namun dalam jangka panjang hal ini tidaklah cukup untuk menggerakkan transformasi nasional secara menyeluruh. Kebutuhan kita akan pasar luar negeri pada beberapa sektor masih cukup tinggi sehingga secara perlahan tapi pasti, berjarak atau tidak, risiko krisis Eropa itu pasti akan menghampiri Indonesia. Hanya saja seberapa cepat krisis itu sampai dan sejauh mana kita bisa mempersiapkan diri agar dampak krisis itu bisa diminimalisir menjadi satu hal yang harus disadari oleh Indonesia ketika Barat menyerukan upaya membagi risiko krisis yang sedang mereka hadapi. Oleh karenanya, Indonesia justru lebih memainkan peranan yang lebih kuat di tengah kelesuan ekonomi Barat seperti sekarang. Secara sosiologis, hal ini bisa bermakna Indonesia sebagai sebuah negara, sekarang memiliki kekuatan yang lebih besar ketimbang masa-masa sebelumnya, untuk tidak saja memasukkan agenda-agenda ekonomi terkait pembangunan nasionalnya tetapi juga mengupayakan memperkenalkan nilai-nilai nasionalnya di tingkat yang lebih universal. Nilai-nilai harmoni di tengah keberagaman atau multikulturalisme barangkali bisa menjadi satu nilai universal yang tidak saja secara teoritis diakui kebenarannya, bagi Indonesia itu adalah praktik sosial sehari-hari yang berlangsung di tengah masyarakatnya dan difasilitasi secara formal oleh negara. Pada tingkat ini, Indonesia akan memberikan sumbangan yang cukup besar bagi konstruksi peradaban dunia masa depan. Di sinilah peranan militer Indonesia menjadi penting dalam rangka menjamin keseimbangan global itu bisa berjalan tanpa harus mengorbankan kepentingan nasional Indonesia.
6.3.
Skenario Tingkat Nasional
Setelah rumusan negara mengenai tantangan dan ancaman global bisa secara gamblang diberikan, selanjutnya barulah kita berbicara mengenai militer Indonesia yang sedang berada pada satu konteks strategis yang dinamikanya sangat tinggi. Oleh karenanya, berangkat dari penjelasan sebelumnya, penting bagi institusi militer Indonesia untuk mendefinisikan kembali problem-problem kekinian yang menjadi ancaman dan tantangan tersebut sebagai bahan dalam menyusun tindakan-tindakan strategis seperti
162
bab5-6 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 162 7/10/12 2:16 PM

apa yang layak untuk dilakukan, termasuk di dalamnya langkah-langkah transformasi
seperti apa yang bisa direncanakan dan dijalankan agar globalisasi yang penuh paradoks
ini bisa dikelola secara optimal.
Merujuk pada penjelasan mengenai transformasi militer di negara-negara lain ada
beberapa catatan pokok yang bisa kita angkat sebagai isu-isu mendasar dari proses
transformasi yang telah dan sedang dilakukan, di antaranya persoalan hubungan antara
otoritas negara dengan institusi militernya, persoalan pendefinisian atas keamanan
nasional negara tersebut, persoalan instrumen transformasi dan perubahan mendasar
yang harus dilakukan di dalam tubuh institusi militer itu sendiri.
Pokok pikiran yang pertama mengenai hubungan antara institusi militer dengan
otoritas negara di Indonesia, kiranya tidak jauh berbeda dengan apa yang berlaku
di negara-negara lain, kecuali mungkin di negara komunis seperti Cina. Posisi
institusi militer Indonesia selama kurun waktu terbentuknya sampai dengan hari
ini, tidak berubah, secara formal TNI berada langsung di bawah Presiden, meskipun
kebijakan-kebijakan terkait keputusan perang ataupun rencana-rencana transformasi
institusionalnya tetap harus melibatkan lembaga-lembaga terkait seperti DPR.55
Perubahan struktur politik pasca reformasi pada gilirannya juga mendorong TNI
untuk berbenah, terutama memutus hubungan antara TNI dengan kebijakan politik
praktis, meskipun fungsi-fungsi politik dari TNI sendiri masih tetap kuat, terutama
terkait tugasnya menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan nasional. Dalam hal ini,
Indonesia telah memiliki postur yang sesuai dengan norma hubungan antara otoritas
pemerintahan yang bercorak sipil dengan institusi militernya. Komitmen reformasi
TNI sendiri telah terinstitusionalisasikan dengan gamblang di dalam Undang-Undang
No. 3 Tahun 2002, meskipun masih ada pro kontra terkait revisi peraturan ini, namun
kewenangan TNI di dalam keputusan-keputusan strategis nasional seperti keputusan
untuk terlibat dalam sebuah perang sepenuhnya berada di bawah kendali presiden
sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara ditambah dengan persetujuan DPR. Tidak
hanya itu, keputusan penetapan Panglima TNI sendiri juga masih harus mendapatkan
persetujuan DPR, yang dalam beberapa hal justru dikhawatirkan malah menyeret TNI
ke ranah politik praktis karena dimungkinkan adanya negosiasi atau kompromi dalam
proses penyetujuan itu.
55 Berdasarkan UU No. 34 tahun 2004, Pasal 3, ayat 1, untuk pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden. Sementara di ayat 2, dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan.
163
bab5-6 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 163 7/11/12 11:37 AM

Terkait dengan persoalan transformasi, hal yang penting untuk diingat adalah ketika institusi militer berada di bawah otoritas sipil, maka otoritas sipillah yang pada prosesnya memiliki kewenangan untuk menyusun rancangan yang dimaksud. Kendati begitu, tidak bisa dilupakan, sesungguhnya gagasan atas reformasi militer Indonesia sebelum tahun 1998 justru berasal dari suara para petinggi TNI yang perduli terhadap kelangsungan masa depan TNI yang profesional. Oleh karenanya, persoalan ini sebaiknya tidak lantas mendikotomikan secara langsung sipil dan militer, karena isu ini jauh lebih politis sifatnya ketimbang substansi yang ada di dalamnya. Keberadaan institusi militer di dalam otoritas sipil harus dimaknai lebih dinamis dengan menempatkan kewenangan militer secara proporsional, namun tetap mengedepankan pemahaman bahwa ancaman terhadap keamanan nasional itu di depan mata, baik yang sifatnya eksternal maupun internal negara.
Memperkokoh supremasi sipil atas militer harus diwujudkan dalam satu cetak biru yang komprehensif, dengan mengedepankan prinsip-prinsip humanisme di dalam institusi militer namun tetap memperkuat basis dan kompetensi kekuatan militer, baik yang bersifat reguler maupun demi kebutuhan-kebutuhan khusus. Selain itu, keberadaan TNI di bawah otoritas sipil sesungguhnya memberikan peluang lebih besar agar TNI bisa lebih berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat kita. Nilai-nilai yang sebelumnya hanya identik dengan institusi-institusi sipil, pada dasarnya bisa juga diterapkan di dalam institusi militer dengan batas-batas tertentu mengingat institusi militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan institusi sosial pada umumnya. Misalnya, hasrat berbagai pihak untuk menciptakan Indonesia yang lebih bersih dan bebas dari KKN, seyogyanya juga bisa dimasukkan di dalam cetak biru reformasi TNI itu sendiri. Oleh karenanya, dalam konteks hubungan kelembagaan ini, prinsipnya adalah menciptakan TNI yang profesional, baik dari sisi organisasi, teknologi maupun sumber daya manusianya. Dalam konteks ini pula, diperlukan satu upaya dari pihak TNI untuk bisa memperjuangkan gagasan mengenai transformasi tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan menjalin komunikasi yang lebih intensif dengan kelompok akademisi dan intelektual yang memiliki perhatian terhadap masa depan TNI yang profesional.
Pokok pikiran yang kedua, mengenai pendefinisian negara atas ancaman dan tantangan keamanan nasionalnya. Permasalahan keamanan yang semakin hari semakin kompleks mestilah dimaknai secara dinamis karena hal ini sangat erat kaitannya dengan dinamika konteks strategis, baik dalam negeri maupun kawasan dan global. Problem peperangan generasi terakhir yang mendorong terorisme untuk juga melakukan upaya-
164
bab5-6 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 164 7/10/12 2:16 PM

upaya kejahatan kriminal demi memenuhi kebutuhan sumber daya mereka, terutama persoalan finansial membutuhkan perhatian yang lebih serius, terutama perihal menyangkut otoritas dan wewenang, kapasitas personel, organisasi dan teknologi yang harus memadai untuk bisa menghadapi ancaman-ancaman tersebut. Namun demikian, persoalan ancaman terhadap kedaulatan nasional pada dasarnya tidak juga mengalami pergeseran yang berarti, konflik-konflik yang terjadi di dunia pada dasarnya masih berkisar pada persoalan-persoalan klasik seperti masalah sengketa perbatasan, perebutan sumber daya alam, dan pengamanan terhadap jalur-jalur distribusi energi. Bahwasanya persoalan ekonomi dan lingkungan seringkali menjadi dasar dari apa yang dinamakan perspektif baru keamanan global, hal ini juga layak untuk mendapatkan perhatian. Intinya, institusi militer Indonesia juga sudah selayaknya diperkenalkan dengan terminologi-terminologi baru dalam dunia keamanan sehingga kesadaran terhadap ancaman ini bisa lebih diwaspadai.
Permasalahan yang harus bisa dijawab dalam upaya merancang proses transformasi militer Indonesia, tentu saja, adalah bagaimana menciptakan kekuatan militer yang mampu melakukan upaya-upaya perang klasik dengan kekuatan tentara reguler dan persenjataan perang skala besar, sekaligus juga bisa menangani persoalan-persoalan baru dalam dunia keamanan seperti terorisme, pembajakan dan isu-isu keamanan lainnya. Kedua hal ini tentu saja sangat mendasar kebutuhannya, karena keduanya bisa sangat berpengaruh pada bentuk organisasi militer yang akan dibangun, sistem persenjataan yang harus diadakan dan doktrin terhadap setiap prajurit itu sendiri. Bagaimana TNI bisa memiliki dua dimensi kompetensi tersebut sekaligus inilah yang harus diperhatikan dalam merancang transformasi institusi TNI masa depan yang tangguh dan profesional.
Pokok pikiran yang ketiga, mengenai instrumen pendukung transformasi. Kebijakan transformasi nasional yang akan dilakukan haruslah didukung dengan satu kekuatan industri persenjataan yang memadai. Kebutuhan industri persenjataan sesungguhnya adalah sebuah pilihan, Indonesia bisa mengandalkan persenjataan tempur dari negara-negara yang terlebih dahulu telah mapan produksi persenjataannya, atau mencoba membangun satu industri pertahanan strategis yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Berkaca dari apa yang telah dilakukan oleh AS dan Eropa serta Cina, apa yang terjadi, jelas memberikan satu gambaran bahwa proses transformasi militer sangat erat kaitannya dengan industri pertahanan setiap negara, baik yang dikelola langsung oleh negaranya, maupun yang dikelola pihak swasta. Dukungan
165
bab5-6 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 165 7/10/12 2:16 PM

industri pertahanan yang kuat selain akan memperkuat basis persenjataan institusi militernya, hal tersebut juga bisa mendorong pembangunan ekonomi nasional serta memperluas produksi nasional untuk orientasi ekspor. Namun demikian, dengan situasi dan kondisi Indonesia dan dunia seperti sekarang, kiranya kita harus bisa lebih bijak dalam menentukan keputusan apa yang hendak diambil. Di antara 2 pilihan tersebut, bahkan kita bisa mengkombinasikannya sehingga hasil yang optimal bisa kita peroleh. Membangun industri persenjataan strategis membutuhkan modal dan upaya yang kuat, jika hal ini belum dilakukan secara 100 %, hasrat pemenuhan kebutuhan persenjataan bisa kita upayakan melalui jalur impor dari negara lain. Namun, rencana dan tahapan kerja yang kongkret dari industri pertahanan nasional tetap harus dilakukan karena perlahan tapi pasti Indonesia harus memiliki industri pertahanan sendiri. Untuk itu sejumlah industri strategis pendukung industri pertahanan nasional harus juga dimiliki dan dikuasai oleh negara sehingga dapat meminimalisir persoalan-persoalan produksi persenjataan di masa depan.
Pokok pikiran yang keempat, perubahan-perubahan mendasar dalam doktrin, organisasi dan teknologi. Berangkat dari tiga pokok pikiran sebelumnya, perlu dibangun satu kerangka dasar dari doktrin militer, serta bentuk organisasi yang efektif untuk menghadapi ancaman-ancaman yang muncul, peningkatan kapasitas individu prajurit terutama dalam penguasaan strategi dan teknologi perang, penelitian dan pengembangan teknologi militer yang relevan untuk mengatasi ancaman keamanan nasional dan yang terakhir tidak kalah pentingnya adalah peningkatan taraf hidup prajurit terutama menyangkut jaminan sosial keluarga prajurit dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Gagasan mengenai RMA itu sendiri, haruslah disesuaikan dengan konteks kultur militer Indonesia.
Keempat pokok pikiran tersebut diharapkan akan bisa dijadikan semacam landasan awal dalam menyusun satu kerangka transformasi militer Indonesia masa depan, yang profesional dan tangguh dalam menghadapi setiap bentuk ancaman terhadap keamanan nasional Indonesia baik yang berasal dari luar (eksternal) maupun dari dalam negeri (internal). Bagi otoritas sipil yang bertanggung jawab dalam proses ini, perlu juga melibatkan kelompok pemikir di dalam tubuh TNI yang menyadari bahwa transformasi TNI itu adalah satu keharusan dalam rangka TNI merespon zaman yang terus berubah.
166
bab5-6 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 166 7/10/12 2:16 PM

6.4.
Rangkuman
Persoalan kemanan nasional saat ini sangat terkait erat dengan masalah atau isu mengenai risiko yang dihadapi oleh setiap negara. Pluralitas risiko itu mengharuskan setiap negara di dunia memperhitungkan akibat serta dampak dari risiko yang mungkin muncul. Atas dampak dan akibat yang mungkin muncul itulah, skenario transformasi sebuah institusi militer harus dibangun. Kegagalan dalam membaca kecenderungan global bukan saja berdampak pada ketidakmampuan sebuah institusi militer untuk menghadapi bahaya keamanan nasionalnya, tetapi hal itu juga bisa memperlambat proses transformasi, atau bahkan menggagalkan rencana transformasi yang telah disusun.
Sebagai sebuah institusi yang keberadaannya di dalam NKRI tidak bisa tergantikan, TNI diharapkan responsif membaca kecenderungan-kecenderungan global yang pergerakannya semakin dinamis. Dinamika ekonomi politik yang di permukaan terlihat melibatkan 2 kekuatan besar dunia, Cina dan AS, penting untuk terus menerus dielaborasi mengenai berbagai kemungkinan yang bisa muncul terkait ketegangan itu. Sejalan dengan apa yang diutarakan oleh Giddens dalam konteks globalisasi sekarang ini, atau jika kita bisa meminjam istilah eklektik Norrin Ripsman dan T.V. Paul dalam menghadapi globalisasi, Indonesia sebagai sebuah negara yang dalam konteks global bisa dilihat sebagai agen atau aktor yang terlibat di dalamnya, semestinya bisa terus terlibat dalam diskusi-diskusi baik di tingkat regional maupun dunia. Diskusi yang dimaksud adalah diskusi yang memiliki bobot cukup besar dalam mendorong munculnya apa yang disebut dengan norma-norma universal. Sebagai sebuah institusi militer yang profesional, TNI, baik individu maupun institusinya, seyogyanya mampu untuk menyumbangkan gagasan-gagasannya dalam konteks membangun aturan dan norma global.
Perhatian terhadap risiko global serta nilai-nilai harmoni yang menjadi landasan hidup sehari-hari masyarakat kita layak diangkat ke permukaan agar dunia menyadari bahwa Indonesia juga memiliki cara pandang terhadap masa depan peradaban manusia yang mungkin lebih baik ketimbang cara pandang arus utama saat ini. Pelajaran berharga yang diperoleh Indonesia ketika membumikan demokrasi bisa menjadi acuan bagi negara-negara lain yang memang masih gamang untuk menerapkan demokrasi di negaranya.
167
bab5-6 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 167 7/10/12 2:16 PM

Kemampuan Indonesia mempertahankan keberagaman di dalam bingkai negara kesatuan, bisa menjadi pelajaran kepada negara-negara yang sampai saat ini masih belum lepas dari konflik identitas. Yang tidak kalah penting dari semua itu adalah pengalaman TNI pasca reformasi, yang secara damai berhasil mengawal proses demokratisasi dan desentralisasi kekuasaan di Indonesia. Pengalaman itu penting bagi negara-negara yang sampai hari ini masih dikuasai oleh junta militer. Tentu saja, kita tidak berharap agar semua resep Indonesia bisa diterapkan atau dijalankan di negara lain, tetapi paling tidak hal itu bisa menginspirasi para pemimpin di dunia untuk menciptakan peradaban masyarakat dunia yang lebih harmonis di masa depan. Kepercayaan diri seperti ini mesti menjadi sebuah national confidence agar mimpi masa depan tentang Indonesia itu bisa segera kita rengkuh.
Selanjutnya, transformasi TNI harus terus menerus diperdebatkan, didiskusikan ataupun diwacanakan. Bukan dalam arti mencari-cari masalah, atau yang dikhawatirkan justru mempolitisasi persoalan di dalam tubuh TNI. Mendiskusikan proses transformasi TNI adalah satu jalan agar TNI betul-betul bisa adaptif dan antisipatif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dunia saat ini. Mendorong TNI menjadi lebih inklusif, terutama dalam hal pemikiran bisa lebih memperkuat kapasitas institusi dan personel TNI.
Di samping itu, tentu saja, sebagai sebuah institusi militer, perdebatan atau diskusi saja tidak akan cukup. Diperlukan sebuah komitmen dari seluruh elemen di republik ini untuk secara konsisten memberikan ruang kepada TNI untuk bisa memperkuat diri agar tugas pokoknya mempertahankan negara dan/atau menjaga keamanan nasional bisa dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Terakhir dan tidak kalah penting dibanding yang lain, adalah memperkuat industri strategis nasional sebagai basis dari industri pertahanan nasional adalah pilihan yang harus diambil oleh otoritas sipil jika kita tidak mau terus menerus bergantung pada industri pertahanan asing. Dalam konteks ini, yang harus disadari oleh kita semua adalah bahwa transformasi TNI tidak mungkin berdiri sendiri. Karena TNI adalah bagian integral dari masyarakat Indonesia, maka rancangan transformasi TNI harus diletakkan di dalam konteks transformasi nasional masyarakat Indonesia yang lebih luas. Transformasi nasional masyarakat Indonesia adalah payung dari transformasi TNI. Hanya dengan cara ini, sinergi antara TNI dan rakyat Indonesia bisa semakin maju dan produktif lagi di masa depan.
168
bab5-6 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 168 7/10/12 2:16 PM

169
bab5-6 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 169 7/10/12 2:16 PM

170
bab7-8 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 170 7/10/12 2:41 PM

Bab VII
Kontribusi Teoritik StudiMiliter• Ikhtiar Mencari Paradigma Globalisasi Khas Indonesia• Melihat Militer dari Perspektif Sosiologik• Kontribusi Pemikiran Globalisasi dalam Khasanah Sosiologi Militer• Cairnya Tembok Sipil-Militer: Kritik atas Huntington• Masa Depan Ranah Kajian Sosiologi Militer• Rangkuman
171
bab7-8 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 171 7/10/12 2:41 PM

Bab VII.
Kontribusi Teoritik Studi MiliterPenjelasan dari awal sampai bagian berikut dari buku ini adalah tawaran yang lebih bersifat praksis bagi satu proses transformatif yang diperlukan untuk militer Indonesia. Seperti dijelaskan di awal bahwa kebutuhan transformasi ini dimaksudkan untuk memperkuat konstruksi militer dalam kontribusinya bagi keutuhan Indonesia maupun dunia.
Sedangkan di luar konteks kebutuhan praksis tersebut, studi ini juga memiliki dampak lain yang tidak kalah penting, yakni sumbangannya kepada teori kajian militer itu sendiri. Bagian berikut ini akan menjelaskan bagaimana sumbangan teoritik tersebut terjadi. Sehingga diharapkan ke depan, hasil dari studi ini akan memberikan pencerahan berkelanjutan bagi sistem militer di Indonesia, maupun masyarakat lain dalam lingkup yang lebih luas.
7.1. Ikhtiar Mencari Paradigma Globalisasi Khas Indonesia
Secara garis besar dari uraian sebelumnya, ketika kita berbicara tentang globalisasi ternyata ada dua aliran utama. Pertama, para teoritisi yang sepakat bahwa globalisasi merupakan representasi dari “imperialisme” Barat atau AS pada bidang ekonomi dan kebudayaan. Dalam bidang ekonomi, mereka mengemukakan bahwa kita tidak bisa menolak masuk dan berkembangnya MNC’s. Walaupun masing-masing teoritisi mempunyai istilah yang berbeda seperti kosmopolistanisme, internasionalisasi ekonomi, atau TNC’s tetapi esensinya sama yakni perluasan ekonomi dan kebudayaan Barat atau AS. Kedua, para teoritisi yang memandang bahwa globalisasi itu bersifat dua arah. Tidak hanya terjadi Amerikanisasi atau Westernisasi, akan tetapi juga muncul reaksi lokal terhadap hal ini, yaitu fundamentalisme. Fundamentalisme ini bisa mengatasnamakan etnis, nasionalisme, ataupun agama. Oleh karena itu, globalisasi tidak hanya memunculkan kosmopolitanisme tetapi sekaligus fundamentalisme.
Dalam konteks ini, maka pandangan Giddens mengenai risiko yang dihasilkan oleh modernisasi akan berdampak secara global, karena terjadi pemisahan antara ruang dan waktu. Kita bisa melihat bagaimana misalnya aksi-aksi fundamentalisme seperti terorisme terkoneksi secara global, dan dengan adanya kemajuan teknologi dan industri persenjataan, maka aksi-aksi mereka pun menjadi lebih canggih. Bagaimana misalnya aksi terror bom Bali berkaitan dengan aksi-aksi terorisme di belahan dunia lainnya.
172
bab7-8 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 172 7/10/12 2:41 PM

Fokus utama yang perlu diperhatikan juga selain proses globalisasi itu sendiri adalah dampak dari globalisasi. Krishner melihat bahwa globalisasi juga sangat berdampak pada keamanan negara. Globalisasi telah merubah aturan main dalam dunia sehingga negara harus mempunyai strategi yang adaptif terhadap ancaman keamanan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Jika suatu negara kurang mencermati dampak globalisasi ini, maka negara tersebut tidak akan mampu memperkirakan perubahan-perubahan keseimbangan kekuatan, prospek peperangan dan pilihan-pilihan yang strategis. Globalisasi juga memiliki kemampuan memaksa suatu negara untuk menyesuaikan kebijakan mereka. Dari beberapa studi empiris yang banyak dilakukan oleh ilmuwan yang fokus pada bidang militer ditemukan bahwa banyak kasus di berbagai negara yang melakukan revolusi dalam bidang militer karena adanya desakan dari NATO seperti di AS dan Kanada (yang merupakan representasi dunia internasional/global) atas nama proses demokratisasi dunia atau menjaga perdamaian dunia.
Kita kembali kepada pandangan Giddens dan Krishner bahwa globalisasi juga mengakibatkan ketidakpastian keamanan. Ancaman persenjataan nuklir atau aksi-aksi terorisme bisa muncul di negara belahan dunia manapun setiap saat. Atau risiko-risiko yang diciptakan dari hasil modernisasi bisa dengan cepat menjadi risiko global. Misalnya perubahan iklim, yang disebabkan menipisnya lapisan ozon akibat emisi industri yang dikeluarkan oleh negara-negara maju melebihi ambang batas yang diijinkan. Karena proses globalisasi melintasi bangsa-bangsa atau jika meminjam istilah Giddens melintasi waktu dan ruang.
Untuk itu, pendekatan Giddens yang memahami globalisasi sebagai berbagi risiko dalam hal ini ketidakpastian keamanan yang dimunculkan oleh konsekuensi yang tidak diharapkan dari proses modernisasi lebih tepat untuk kita jadikan basis untuk membuat rancang besar kebijakan militer di Indonesia. Karena muara dari kebijakan ini adalah kerjasama internasional. Seluruh negara bersama-sama mengatasi ancaman ketidakpastian keamanan. Akan tetapi, basis yang paling utama ketika kita berbicara tentang globalisasi dalam konteks Indonesia; keamanan dan kepentingan nasional merupakan basis utamanya sehingga militer Indonesia didorong untuk menjadi agen dalam keamanan internasional. Caranya dengan meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan personel serta organisasi militernya termasuk di dalamnya juga teknologi. Tentu, proses ini akan lebih efektif jika kita juga mampu mempunyai industri persenjataan perang sendiri yang produktif.
Berangkat dari penjelasan teoritik di atas, kiranya bagi negara berkembang seperti Indonesia, globalisasi lebih layak untuk dilihat sebagai satu proses yang selain di dalamnya penuh dengan ketidakpastian dan segudang risiko, ia juga bisa memfasilitasi secara baik munculnya inisiatif-inisiatif positif di dalam proses perkembangan
173
bab7-8 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 173 7/10/12 2:41 PM

satu peradaban manusia, betapapun kecilnya. Daya fasilitasi yang baik inilah yang sesungguhnya bisa dijadikan sebagai modalitas bagi Indonesia dalam melihat persoalan internasional secara lebih optimis. Terkait dengan dikotomi ilmuwan -- kiri dan kanan -- yang mencoba menelaah globalisasi lebih jauh, mengutip apa yang dikatakan dalam penelitian Ripsman and Paul, sepertinya diperlukan satu upaya yang lebih berbasiskan pada proses empirik dalam melihat dan memaknai globalisasi sehingga kita tidak terjebak pada definisi-definisi yang relatif kaku dari para ilmuwan yang telah mapan dalam mendefinisikan globalisasi. Singkatnya, globalisasi sendiri tidak hanya mampu memaksa, tetapi juga dia membiarkan dirinya untuk bisa dikelola dan dimanfaatkan oleh siapapun.
7.2. Melihat Militer dari Perspektif Sosiologik
Pertanyaan yang akrab kita dapati ketika seorang sosiolog membahas tentang militer (sosiologi militer): apa yang membedakan kajiannya dengan ahli politik atau ahli ekonomi ? Tentu saja yang membedakannya adalah perspektifnya atau pendekatannya. Dalam sosiologi militer terdapat dua pendekatan dominan dalam melihat militer. Pertama, lebih difokuskan kepada hubungan antara masyarakat sipil dan militer. Pionirnya adalah Samuel Huntington. Sedangkan pendekatan yang Kedua lebih fokus kepada organisasi. Militer dilihat sebagai salah satu bentuk organisasi sosial. Pendekatan ini diprakarsai oleh Morris Janowitz.
Dalam karyanya The Soldier and The State pada tahun 1957, Huntington mencoba menganalisis bagaimana interaksi antara kekuatan militer dengan otoritas masyarakat sipil, baik di negara-negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokratis maupun di negara-negara yang masih dalam tahap mencapai sistem pemerintahan yang demokratis seperti negara-negara di Afrika Selatan. Sedangkan Janowitz melalui karyanya The Profesional Soldier tahun 1960 mengemukakan bahwa analisis institusi tidak hanya mencakup institusi militer (perang dan damai) tetapi juga mencakup relasi militer dan masyarakat sipil, pengurangan angkatan atau senjata perang, misi penjagaan perdamaian, serta menajemen dan reduksi konflik. Janowitz juga menegaskan bahwa masyarakat itu sangat dinamis sehingga dunia militer pun harus mempunyai daya adaptasi yang tinggi. Janowitz menyimpulkan bahwa organisasi militer di Barat semakin meningkatkan keprofesionalitasan mereka, baik dalam sikap maupun keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi sebagai militer yang modern.
174
bab7-8 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 174 7/10/12 2:41 PM

Ketika kita membahas perspektif yang dominan dalam sosiologi militer, lantas muncul pertanyaan bagaimana posisi sosiologi militer itu sendiri dalam ilmu sosiologi. Caforio (2003) mengemukakan bahwa sosiologi militer merupakan sub bagian dari sosiologi. Ia menempati posisi seperti sosiologi pendidikan, sosiologi agama, dan sosiologi gender. Akan tetapi argumentasi yang dibangun oleh Caforio ini kurang mumpuni untuk menjelaskan misalnya fenomena tentang perempuan dalam militer, yang hanya dapat dijelaskan melalui pendekatan sosiologi gender. Atau relasi antara militer dan masyarakat sipil yang dapat dijelaskan oleh pendekatan sosiologi politik. Dengan adanya realitas demikian, maka para sosiolog yang mendalami kajian tentang militer menyepakati bahwa posisi sosiologi militer masuk ke bidang sosiologi umum dalam bentangan disiplin ilmu sosiologi (Eric, 2005) sehingga mereka lebih fleksibel untuk memanfaatkan analisis-analisis sosiologi tentang militer.
Dalam konteks buku ini, jika mengacu pada pada dua perspektif sosiologik itu, pertanyaannya kemudian adalah akan diletakkan di manakah proses transformasi militer dan RMA yang telah dibahas sebelumnya.
Pembahasan mengenai transformasi militer pada gilirannya tidak hanya berkutat pada bagaimana organisasi militer bisa adaptif atau mampu menjawab persoalan-persoalan keamanan yang sifatnya dinamis. Transformasi militer sendiri dalam perjalanannya terkait erat dengan bagaimana sistem politik yang dianut oleh satu negara dan relasi satu negara dengan kelompok negara yang termasuk ke dalam kekuatan besar dunia. Namun demikian, dari penjelasan rinci yang telah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya kita bisa tarik satu pelajaran yang bisa dijadikan sebagai satu ikhtiar untuk menjembatani antara dikotomi perspektif sosiologik dalam melihat ranah kajian sosiologi militer dengan upaya untuk mencari bentuk baru studi militer dalam perspektif sosiologik yang menempatkan organisasi militer sebagai organisasi pada umumnya. Organisasi militer yang dinamika internalnya tidak bisa begitu saja dipisahkan dengan dinamika dunia di luar organisasi itu sendiri. Dalam kata lain, tidak lagi sebagai organisasi militer yang sebelumnya kita kenal tertutup ataupun memiliki kecenderungan yang sulit diintervensi oleh pihak dari luar. Pemahaman ini sekarang sepertinya sudah tidak lagi layak untuk dilihat, karena fakta menunjukkan bahwa organisasi militer merupakan kelompok organisasi yang paling adaptif terhadap apa yang dinamakan sebagai ancaman, baik ancaman institusional maupun ancaman nasional. Strategi dan proses yang telah di-wargaming-kan secara matang pasti kemudian akan diambil sebagai sebuah kebijakan ketika menghadapi persoalan seperti itu. Selain itu, organisasi militer juga adalah pihak yang paling cepat merespon kebutuhan teknologi karena peralatan perang semakin hari semakin canggih, sehingga bagi organisasi militer yang tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi persenjataan
175
bab7-8 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 175 7/10/12 2:41 PM

ataupun teknologi militer sudah bisa dipastikan akan menjadi terbelakang dan tidak akan mampu berkompetisi dengan organisasi militer lainnya.
Melihat militer secara sosiologis sedikit banyak juga memberikan kita sebuah cakrawala berpikir yang lebih kritis untuk melihat betapa batas-batas antara ilmu pengetahuan sosial seringkali cair atau tidak tegas. Entah batas-batas ini memang sedari awalnya tidak tegas, ataukah memang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri yang pada prosesnya mengarah pada semakin pudarnya batas-batas tersebut. Seperti halnya globalisasi yang mengarahkan kita pada semakin cairnya batas-batas negara. Ataupun kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi yang telah berhasil memampatkan ruang dan waktu atau menghilangkan batas antara ruang privat dan ruang publik. Mengenai studi militer sendiri, kita bisa melihat bagaimana bahasan-bahasan yang dilakukan oleh para sarjana ilmu politik dan sejarawan seringkali tidak secara eksplisit mengabstraksikan persoalan-persoalan yang muncul dalam studinya untuk merepresentasikan konsep-konsep utama dalam ilmu sosiologi, tetapi jika yang membacanya adalah seorang sosiolog hal itu bisa nampak atau muncul sebagai isu sosiologis.56 Demikianlah kiranya, memahami militer dari sudut pandang sosiologis pada akhirnya mengarahkan kita pada isu paling sensitif dari batas-batas imajiner ilmu pengetahuan sosial itu sendiri.
7.3. Kontribusi Pemikiran Globalisasi dalam Khasanah Sosiologi Militer
Pada bagian ini kita akan membahas pertanyaan sentral dalam buku ini. Bagaimana pemikiran mengenai globalisasi memberikan kontribusi terhadap khasanah sosiologi militer? Seperti kita bahas sebelumnya bahwa ada dua perspektif yang dominan dalam sosiologi militer yakni yang pertama fokus kepada relasi antara masyarakat
56 Cairnya batas-batas antar disiplin ilmu sosial ini (sosiologi dengan ilmu sosial yang lain), juga kita bisa lihat dalam kajian terbaru tentang militer yang dilakukan oleh Muhadjir Efendy (2008) tentang jatidiri dan profesi TNI. Walaupun menggunakan pendekatan dominan antropogi, ia tidak bisa mengabaikan pendekatan Weberian dalam kajiannya. Ia menemukan bahwa pemahaman mengenai profesionalisme TNI tidak sama. Walaupun faktanya sistem yang berlaku adalah sistem komando. Perbedaan pengalaman baik dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan area penugasan berpengaruh terhadap pemahaman tentara terhadap profesionalisme militernya. Atau buku karangan Wawan Purwanto (2011) “TNI dan Tata Dunia Baru Sistem Pertahanan” yang lebih bisa diklasifikasikan sebagai membedah TNI dari sudut pandang kajian pertahanan, ternyata begitu banyak menyebutkan konsep-konsep kepemimpinan dalam tubuh TNI. Begitu juga kajian sejarah Ulf Sundhausen (1982) mengenai politik militer Indonesia yang masih menitik beratkan analisisnya pada persoalan kelompok elite militer Indonesia.
176
bab7-8 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 176 7/10/12 2:41 PM

sipil dan militer, dan yang kedua, memandang militer sebagai salah satu bentuk organisasi sosial. Kita akan bertitik tolak dari pendekatan yang kedua, yaitu militer merupakan sebuah organisasi sosial. Karena, pendekatan ini lebih holistik daripada pendekatan sebelumnya. Melalui perspektif ini, bahasan kita tidak hanya mencakup institusi militer akan tetapi juga relasi militer dengan masyarakat sipil, pengurangan angkatan atau senjata perang, misi penjagaan perdamaian, serta menajemen dan reduksi konflik. Artinya, kita menggunakan pendekatan Janowitz. Bagaimana kaitannya dengan globalisasi? Seperti pembahasan kita sebelumnya, kita memahami bahwa globalisasi adalah berbagi risiko, terutama mengenai risiko ketidakpastian keamanan yang dimunculkan oleh konsekuensi yang tidak diharapkan dari proses modernisasi sehingga kita harus melakukan kerjasama dengan negara-negara di dunia untuk mengatasi berbagai risiko tadi. Karena dengan adanya globalisasi risiko tadi melintasi ruang dan waktu, atau dengan kata lain melintasi batas-batas negara. Globalisasi tidak hanya memunculkan kosmopolitanisme akan tetapi juga fundamentalisme. Sehingga institusi militer akan beradaptasi dengan melakukan transformasi untuk merespon risiko-risiko yang berskala global tersebut. Institusi militer harus merestrukturisasi diri lagi sehingga bisa beradaptasi. Atau dalam tataran yang lebih luas, globalisasi mempunyai kekuatan yang memaksa negara-negara, khususnya institusi militernya untuk melakukan perubahan, baik itu dalam perubahan kapasitas kepemimpinan dan personel maupun teknologi dan organisasinya, termasuk di dalamnya doktrin. Dengan kata lain, globalisasi menuntut adanya perubahan dalam organisasi militer agar mereka bisa merestrukturisasi dunia sehingga risiko tadi dapat diperkecil. Hal ini memaksa negara (organisasi militer) untuk bertransformasi menjadi agen dalam restrukturisasi tersebut.
Oleh karena itu, secara singkat bisa dijelaskan bahwa sumbangan terbesar dari kajian-kajian kontemporer mengenai globalisasi oleh para ilmuwan adalah kecenderungan pengaruh global terhadap kondisi keamanan dunia dewasa ini telah mendorong satu pemahaman baru bahwa sesungguhnya organisasi militer adalah organisasi yang secara sosiologis memiliki kecenderungan yang jauh lebih adaptif ketimbang organisasi sosial manapun, terutama ketika berada pada konteks permasalahan yang spesifik seperti ancaman terhadap keamanan nasional suatu negara yang bentuk dan jenisnya pun terus menerus mengalami perubahan.
Tetapi harus diakui bahwa dalam beberapa hal militer harus memperhitungkan persoalan informasi dan komunikasi baik antar individu di dalam institusinya maupun dengan institusi di luar militer, apakah itu negara ataupun organisasi-organisasi lainnya. Di sini, militer memiliki kepentingan untuk menutup akses informasi karena hal ini berkait erat dengan konteks strategis yang sedang mereka hadapi, sehingga secara
177
bab7-8 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 177 7/10/12 2:41 PM

singkat kita bisa katakan, meskipun kecenderungan militer itu tertutup karena ada satu kepentingan yang menjadi pertimbangan khusus, tetapi tidak bisa dipungkiri sekali lagi bahwa mereka adalah institusi yang harus paling depan dan adaptif dengan tantangan-tantangan baru di masyarakat, baik masyarakat di dalam negeri ataupun masyarakat global. Dengan kenyataan bahwa militer adalah juga organisasi yang memiliki kecenderungan adaptif yang lebih ketimbang organisasi lainnya, ada konsekuensi lanjut dari pernyataan tersebut. Layaknya sebuah organisasi yang adaptif untuk merespon persoalan-persoalan yang akan datang dan harus dihadapi, maka analisis informasi yang akurat menjadi kebutuhan yang sangat mendasar dan menentukan untuk mengantisipasi kecenderungan-kecenderungan yang mungkin muncul di masa depan.
Dalam konteks mendapatkan informasi yang valid dan analisis yang jitu itulah hal paling mendasar yang pasti dilakukan adalah membangun diskursus ataupun menjaring informasi sehingga militer bisa tanggap terhadap persoalan-persoalan yang muncul. Memang institusi ini tidak bisa dikatakan terbuka secara seratus persen, namun dengan adanya proses dialektika yang terbangun secara terus menerus -- karena mengingat tantangan dan ancaman keamanan juga bersifat reproduktif -- institusi militer juga secara institusional harus memiliki kemampuan untuk bisa mereorganisasi diri sesuai dengan ancaman dan tantangan yang muncul. Dengan adanya kenyataan bahwa zaman terus bergulir, institusi militer bisa dipastikan menjadi organisasi yang secara internal memiliki dinamika yang tinggi. Individu-individu yang ada di dalam komunitas militer, sudah bisa dipastikan adalah individu-individu yang secara terus menerus berhadapan dengan isu-isu terkini dari persoalan nasional dan global. Individu yang secara sosiologis sesungguhnya memiliki kemampuan untuk membangun jaringan, mengakses informasi terkini dan mendefinisikan serta menganalisis situasi secara cepat dan tepat. Individu yang dalam segala hal bisa dikatakan sebagai individu aktif, agen kooperatif (dalam istilah Margaret Archer), atau aktor dominan (dalam bahasa Bourdieu). Berangkat dari penjelasan ini, maka tidak salah lagi bahwa jenis agen atau individu yang memiliki kecenderungan kuat seperti inilah yang dibutuhkan untuk menjadi agen pendorong dari proses transformasi di dalam tubuh militer.
7.4. Cairnya Tembok Sipil-Militer: Kritik atas Huntington
Pemilahan antara dua level skenario itu tentu saja bukan dalam kerangka membuat prioritas sehingga salah satunya menjadi lebih penting ketimbang yang lainnya. Pemilahan itu dilakukan semata-mata untuk membangun satu rancangan strategis yang lebih terfokus. Karena sesungguhnya kedua level skenario itu satu sama lainnya saling
178
bab7-8 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 178 7/10/12 2:41 PM

terhubung mengingat persoalan global dan nasional bahkan lokal, jika kita merujuk pada penjelasan para ilmuwan di awal, memiliki cara dan gaya relasinya sendiri sehingga tidak mungkin terjadi keterpisahan.
Pada bagian ini, memang tidak secara spesifik membahas persoalan hubungan sipil dengan militer. Padahal apabila prinsip-prinsip di atas dijalankan, konsekuensi logis dari hal itu akan sampai pada isu yang dominan dalam khasanah sosiologi militer, yakni hubungan sipil dan militer. Salah seorang pemikir dari isu ini seperti yang tadi sudah disinggung, adalah Samuel Huntington, dengan gagasan kontrol subyektif dan obyektif otoritas sipil terhadap militer. Dalam hal ini, Huntington yang melihat sipil dan militer sebagai dualisme institusi yang menghantui persoalan-persoalan demokrasi di negara-negara yang baru saja lepas dari rezim otoritarian mengemukakan pilihan-pilihan rasional yang bisa diambil agar proses demokratisasi berjalan dengan lancar dan supremasi sipil dalam arti yang substantif bisa berlangsung.57
Jika pembahasan ini dipaksakan untuk masuk pada ranah kajian hubungan sipil dengan militer, kiranya kita bisa melihat bahwa persoalan relasi antara keduanya, dalam konteks pendekatan buku ini jelas akan mengarah pada satu situasi di mana keduanya tidak berada pada posisi yang saling menegasikan antara satu dengan yang lainnya. Secara faktual, kita bisa melihat bahwa dalam perkembangan Indonesia pasca reformasi, otoritas sipil memang semakin hari semakin memperoleh porsi kekuasaan yang relatif besar, sedangkan sebaliknya militer Indonesia mulai menanggalkan “jubah” kekuasaan yang sebelumnya mereka kendalikan pada masa Orde Baru kepada pihak sipil. Kendati demikian, keterpisahan itu tidak serta merta menghapus jejak-jejak militer dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sebagai salah satu institusi sosial yang ada di Indonesia, militer dan birokrasi diakui sebagai lembaga yang mampu melahirkan kepemimpinan yang efektif ketimbang partai politik sebagai representasi kekuatan sipil. Barangkali periode ini masih bisa kita katakan sebagai periode transisi yang tidak lantas bisa menghapus secara total kekuatan militer dalam dunia politik, tetapi bukan tidak mungkin hal ini justru sebuah antitesis dari pemisahan secara ketat yang dilakukan oleh Huntington. Walaupun jika hal ini dianggap sebagai satu proses transisi yang belum usai, paling tidak kita bisa menyaksikan dalam beberapa hal, kepemimpinan sipil tidak lantas bisa
57 Konsep kontrol sipil subyektif dan kontrol sipil obyektif bagi Huntington adalah pilihan yang bisa diambil oleh negara yang mayoritasnya menghendaki terjadinya supremasi sipil dalam sistem politik kenegaraannya. Upaya ini bisa dilakukan bukan tanpa syarat, perlu ada tindakan-tindakan kongkret yang dilakukan, baik oleh kalangan politisi sipil maupun para pemimpin militernya. Secara subyektif, Huntington mendorong lebih maju apa yang dinamakan dengan kontrol sipil obyektif, karena dengan hal ini, konflik dan ketegangan yang pasti ada bisa sedikit diminimalisir. Namun demikian, hal ini bukan tanpa risiko karena dari kelompok politisi sipil sendiri seringkali membuka peluang dan kesempatan bagi para pemimpin militer untuk bisa terlibat dalam pembagian kekuasaan dengan tujuan menjaga stabilitas kekuasaan politiknya.
179
bab7-8 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 179 7/10/12 2:41 PM

secara efektif mengatasi berbagai persoalan, sebaliknya, kepemimpinan militer juga tidak senantiasa buruk. Atau dalam penjelasan yang lain, kita bisa mendapatkan satu gambaran bahwa persoalan tradisi politik sipil dan tradisi politik militer tidak serta merta bersifat kaku atau terpisahkan dalam batas yang tegas. Dalam hal ini, penulis ingin mengatakan bahwa globalisasi telah mencairkan secara perlahan batas antara “yang sipil” dan “yang militer”.
Mengapa globalisasi bisa memiliki daya sedemikian kuat untuk menembus batas-batas yang semula kaku dan tegas menjadi relatif cair, bahkan seringkali absurd. Penjelasan di bawah ini menjadi semacam ilustrasi bagaimana globalisasi itu bekerja secara efektif, meniadakan yang ada dan sekaligus mengadakan yang tiada.
Dalam konteks Indonesia, dikotomi tegas antara militer dan sipil termasuk relasi sosial yang terjadi di antara keduanya bisa disebut sebagai pemahaman baru yang muncul seiring proses reformasi pasca 1998. Selanjutnya, konsep tersebut sesungguhnya sangat politis ketimbang sosiologis. Secara politis, keduanya memang bisa dilihat secara jelas dalam representasi kehadiran negara di tengah masyarakat. Dengan kekuatan kontrol yang melekat di dalam atribut kemiliteran yang oleh berbagai kalangan dilihat sebagai peralatan negara yang efektif untuk membangun kepatuhan rakyat, terutama di masa Orde Baru, anggota militer seperti memiliki privilege yang berlebihan di tingkatan masyarakat. Kekuasaan absolut Orde Baru yang menghadirkan begitu banyak kekuatan tentara di dalam struktur pemerintahan memunculkan dorongan yang begitu kuat untuk membangun supremasi sipil pasca 1998. Namun secara sosiologis, di dalam masyarakat Indonesia sekarang ini, terutama di wilayah perkotaan, hampir bisa dipastikan privilege itu tidak lagi bisa dirasakan oleh kelompok tentara. Meskipun agak terlalu dini untuk langsung mengatakan bahwa globalisasilah yang telah mendorong semua ini terjadi, namun tidak bisa kita kesampingkan, bahkan di masa Orde Baru masih berkuasa, tidak jarang kita menemui anggota TNI yang mengalami persoalan sosial yang sama dengan masyarakat pada umumnya, terutama terkait dengan kesejahteraan. Apalagi selepas reformasi bergulir, citra institusi militer begitu terpuruk sehingga bentuk-bentuk penghargaan dari masyarakat kepada militer mengalami proses degradasi. Tidak jarang kita melihat berita-berita di media massa yang memperlihatkan dalam derajat tertentu anggota militer aktif maupun anggota militer yang sudah pensiun mengalami persoalan-persoalan ekonomi lumrah seperti rakyat kebanyakan, bahkan dalam beberapa hal keluarga anggota militer yang sudah pensiun mesti berhadap-hadapan dengan negara untuk menuntut keadilan. Jika persoalannya kemudian adalah kapitalisasi simbol-simbol kekuasaan dalam interaksi sosial di masyarakat, kiranya tidak hanya militer yang bisa melakukan hal itu, anggota masyarakat dari kelompok mana pun saat ini terbiasa mengkapitalisasi simbol-simbol serta status sosial yang mereka miliki akibat posisi atau jabatan mereka pada institusi-institusi lain selain institusi negara, seperti partai politik maupun organisasi massa.
180
bab7-8 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 180 7/10/12 2:41 PM

Contoh yang paling kongkret mengenai sosok militer di ranah sipil, tentu saja Presiden SBY, yang telah mampu mendorong satu tradisi kepemimpinan yang melembagakan nilai-nilai non militer (sipil) dalam konstruksi kenegaraan di Indonesia. Terlepas adanya ketidakpuasan dari berbagai kalangan dalam dua periode kepemimpinannya, hal itu justru dimaknai sebagai konsekuensi logis dari berkembangkannya nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Bukan hanya membangun organisasi pemerintahan sipil di Indonesia, Presiden SBY juga berhasil melembagakan secara kongkret nilai-nilai demokrasi serta mempromosikan perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia ke ranah internasional.58 Pada lingkup sosial yang lebih spesifik, barangkali kita juga bisa melihat peran seorang militer di ranah sipil dalam konteks yang lebih kontemporer, yakni Rahmad Darmawan, seorang Kapten Marinir dari TNI AL, yang telah berhasil membawa Tim Nasional PSSI Usia 23 masuk ke babak final SEA GAMES 2011. Meskipun kalah dari Malaysia dalam drama adu penalti, tetapi tidak seorang pun masyarakat sepakbola di negeri ini yang menganggap hal itu adalah kegagalan dari RD, sapaan akrab Rahmad Darmawan. Justru masyarakat menganggap RD adalah sosok yang telah sangat berjasa membawa kejayaan bagi Timnas. Gelombang simpati masyarakat muncul ketika ia akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisi pelatih Timnas karena merasa gagal membawa Timnas menjadi juara serta adanya persoalan internal di dalam tubuh organisasi PSSI. Dua contoh kepemimpinan militer di ranah sipil di atas, tentu tidak bisa digeneralisasi untuk menunjukkan bahwa setiap orang militer pasti memiliki kapasitas kepemimpinan yang bermutu di ranah sipil. Tidak jarang, banyak juga orang militer yang justru gagal berada di ranah sipil, atau justru terjerat kasus korupsi atau kriminal lainnya. Tetapi, dari apa yang telah dikemukakan mengenai SBY dan RD, hal ini juga mengetengahkan satu realitas sosial yang hidup dan berkembang di negeri ini, bahwa soal kepemimpinan, soal kapasitas, soal dedikasi dan integritas menyangkut hal apapun, dikotomi sipil militer tentu tidak lagi relevan untuk dikemukakan.
Kendati dalam beberapa hal, organisasi atau institusi tempat seseorang belajar dan berkembang pasti memberikan pengaruh yang cukup kuat bagi individu yang berada di dalamnya ketika berpikir, merasa dan bertindak, konteks sosial yang lebih
58 Implementasi nilai-nilai demokrasi di Indonesia sejalan dengan keberhasilan Pemilu secara langsung yang hasilnya ternyata menempatkan Presiden SBY sebagai presiden yang meraih suara terbanyak dibandingkan para pemimpin dunia lainnya. Menurut Majalah Veja (mingguan terbesar di Brazil terbit sejak 1969, sekelas Time di AS dan Tempo di Indonesia) pada edisi 26 Oktober 2011 menulis sebagai berikut: “. . . . . Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono is the ruler of world history with the most votes in absolute terms. His re-election - the second free elections in Indonesia - for a second term of 5 years, 8 July 2009, with 73.8 million votes, second place went to his own feat of five years before, and won 66, 3 million votes. The second is U.S. President Barack Obama, with 69.4 million votes cast in
181
bab7-8 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 181 7/10/12 2:41 PM

luas dari organisasi itu sendiri juga berperan dalam mengkonstruksi individu tersebut. Dalam hal Indonesia, meskipun institusi militer mengembangkan prinsip dan nilai-nilai militeristik di dalamnya, tetapi dalam konteks yang lebih luas, Indonesia telah berubah, demikian juga halnya dengan TNI yang telah berubah dan menyesuaikan diri dengan konteks yang lebih besar tersebut.
Pemikiran seperti ini, ternyata juga terjadi di dunia Barat. Penjelasan Rukavishnikov dan Pugh (2006:133) menunjukkan bahwa di Barat saja, tidak ada solusi tunggal yang bisa menyelesaikan persoalan kontrol demokrasi terhadap militer. Mereka berdua mengingatkan bahwa konstruksi politik dan hukum dari relasi militer-sipil (civil-military relation) sangat ditentukan oleh keragaman karakteristik negara seperti, sejarah tradisi negara tersebut, utamanya sejarah militer di tempat itu, kemudian evolusi landscape politik internal negara dan tentu saja kondisi lingkungan keamanan internasional, terkait hubungan satu negara dengan sekutu-sekutunya (alliances). Terakhir, situasi politik sangat ditentukan oleh personel-personel di dalam tubuh militer dan para pemimpin nasional, dalam konteks hubungan itu, informal relationship menjadi sedemikian penting.
Apa yang dikemukakan Rukavishnikov dan Pugh menjadi semacam penanda bagi kita untuk juga bisa lebih dalam memahami konsepsi civil-military relation. Artinya, sebagai sebuah konsep yang diimpor dari luar, pandangan ini sudah selayaknya dikontekstualisasikan dengan karakteristik nasional kita yang cukup beragam.
2008. It follows in third place in the list of elected champions of votes, the very Susilo and 66.3 million votes in 2004. The fourth place is the former U.S. president George W. Bush in his reelection in 2004 with 60.6 million. Brazil is well on the list: the fifth is best placed Lula re-election in 2006, when it reached 58.2 million votes. In this ranking, it is up to sixth place and its President Rousseff 55,700,000 elections last October. The seventh, the late President Ronald Reagan, elected in 1984 with 54.4 million votes. The eighth position is also Lula in 2002, with 52.7 million votes. With two exceptions, the other champions of votes of all time is American, since, among countries of the larger population of the United States, or no presidentialism (India), or there is no democracy (China). And of course, the list order is relative, because the more recent the president-elect, he has been most benefited by population growth. The list is as follows: Russian President Dmitri Medvedev, with 52.5 million votes in 2008. George W. Bush, in his first election in 2000, with 50.4 million; Russian President Vladimir Putin on his re-election in 2004, with 49.5 million; George Bush in 1988, with 48.8 million; Bill Clinton, when reelected in 1996 with 47.4 million; Richard Nixon re-election in 1972, with 47.1 million; Ronald Reagan in his first election in 1980, with 43.9 million; Jimmy Carter almost enters the relationship, with 40.8 million achieved in 1976. Fernando Henrique Cardoso was the next reelection in 1998, with 35.9 million. The record could theoretically fall back in March of next year, when they make themselves the next presidential elections in Russia, if the likely candidate - Putin - has a large percentage of votes, although it is almost impossible to reach 73.8 million of Indonesian Susilo. The cop, insists it will come in November of next year, when Obama seek re-election in the United States, which has an electorate far more numerous than the Russian. It is possible that the record falls, as the U.S. population - 312 million - far exceeds that of Indonesia, with its 243 million.. . . . . .“
182
bab7-8 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 182 7/10/12 2:41 PM

Pada gilirannya mempertimbangkan faktor-faktor yang telah disebutkan oleh Rukavishnikov dan Pugh dalam konteks Indonesia harus dilakukan, bukan untuk menenggelamkan konsep tersebut atau justru sebaliknya, mempertajam friksi di antara sipil dengan militer, tetapi lebih kepada mencari jembatan penghubung yang bisa menempatkan dua struktur itu di dalam satu konstruksi sosial yang produktif bagi Indonesia di masa depan. Apalagi ketika kita sama-sama dihadapkan pada tantangan globalisasi yang penuh risiko.
Berangkat dari penjelasan di atas, jika konsepsi keterpisahan militer sipil itu jauh lebih politis sifatnya, lantas di mana sesungguhnya peranan globalisasi dalam mencairkan batas psikologis dan sosiologis dari militer dan sipil dalam ranah kehidupan sehari-hari di masyarakat.
Globalisasi dengan beragam dampaknya, terutama menyangkut teknologi informasi dan komunikasi, saat ini bisa dikatakan melampaui cerita-cerita klasik mengenai keistimewaan militer dalam dinamika interaksi sosial. Jika sebelumnya militer adalah satu-satunya institusi yang memiliki otoritas dan kewenangan secara penuh untuk bisa menggunakan ataupun mengakses teknologi informasi dan komunikasi canggih, saat ini cerita itu sudah tidak lagi berlaku untuk kasus Indonesia. Dalam beberapa hal, kelompok swasta maupun kelompok memiliki kemampuan yang tidak kalah canggih dalam hal mengakses informasi maupun melakukan komunikasi dengan siapapun. Institusi militer yang selama ini memiliki kecenderungan untuk seolah tertutup terkait informasi dari dan ke luar, saat ini bisa dikatakan tersaingi oleh kemampuan banyak pihak dalam menggunakan peralatan komunikasi yang super canggih. Dalam konteks ini, institusi militer yang semula memiliki keistimewaan dalam mengakses informasi terkadang kalah canggih dibanding kelompok-kelompok maupun individu yang memiliki kepandaian lebih dalam hal mengakses informasi. Padahal seperti kita ketahui, abad ini adalah abad informasi, siapa yang lebih bisa mengakses dan menggunakan informasi itu, ia akan lebih unggul dibanding yang lain, sehingga kita bisa katakan bahwa globalisasi telah meratakan beberapa kemampuan-kemampuan khusus yang sebelumnya hanya dimiliki oleh institusi militer. Sekali lagi, upaya teoritis ini terbatas pada konteks Indonesia sebagai negara berkembang. Karena itu, dikotomi sipil-militer versi Huntington, barangkali mesti ditinjau secara lebih kritis, terutama ketika kita akan menggunakannya dalam konteks Indonesia.
183
bab7-8 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 183 7/10/12 2:41 PM

7.5. Masa Depan Ranah Kajian Sosiologi Militer
Melihat militer dari perspektif sosiologik, yakni menggunakan pendekatan-pendekatan yang sangat dikenal dalam khasanah ilmu sosiologi secara kuantitatif masih sedikit. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, institusi militer membutuhkan uluran tangan dari para sosiolog untuk bisa lebih membedah permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya dalam kerangka mendorong proses transformasi menuju militer Indonesia yang lebih profesional, inklusif dan tangguh. Kendati begitu, sejauh mana prospek ilmiah sosiologi militer bisa berarti bagi proses transformasi di dalam tubuh institusi militer Indonesia menjadi salah satu pertanyaan yang penting untuk kita elaborasi dan carikan jawabannya bersama-sama.
Selama ini, para ilmuwan yang membedah persoalan militer Indonesia, lebih banyak yang menggunakan perspektif ilmu politik, sejarah maupun kajian keamanan (security studies), sebut saja studi-studi yang dilakukan oleh Sundhausen (1982), Notosusanto (1974), Crouch (1978) ataupun Singh (1995,1999) ataupun para pemikir lainnya. Sedangkan yang mencoba untuk masuk lebih dalam ke ranah militer sebagai institusi sosial di mana di dalamnya terjadi interaksi sosial khas militer masih sangat kurang. Perdebatan mengenai militer Indonesia lebih dominan diarahkan pada bagaimana relasinya dengan kekuatan politik maupun interaksi mereka dengan masyarakat. Barangkali hal ini sedikit banyak dipengaruhi oleh masa-masa rezim Orde Baru yang memang memposisikan militer begitu sentral dalam setiap kehidupan masyarakat karena dari mulai Presiden sampai kepala desa, militer memegang kendali cukup kuat. Oleh karenanya, dengan konteks yang sangat berbeda seperti dewasa ini ketika kita bisa menyaksikan betapa kebebasan begitu menyeruak sampai ke pelosok-pelosok dan sendi-sendi kehidupan masyarakat, mengalihkan perhatian kita kepada proses-proses sosial yang terjadi di dalam tubuh militer Indonesia akan sangat bermanfaat. Bukan saja demi terciptanya pengetahuan yang menyangkut sosiologi militer itu sendiri, melainkan juga terkait dengan bagaimana kita bisa membantu membangun satu postur militer Indonesia yang sesuai dengan perkembangan zaman. Memperlakukan militer sebagai layaknya insitusi sosial lain, secara akademik akan memberikan peluang bagi kita untuk bisa mengelaborasi banyak hal yang selama ini cenderung tertutup ataupun terkesan tabu untuk diperdebatkan di dalam ranah militer.
Singkatnya, mengembangkan ranah kajian sosiologi militer dalam hal ini
184
bab7-8 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 184 7/10/12 2:41 PM

bertujuan untuk membantu institusi militer melakukan proses transformasi sesuai dengan apa yang sedang ataupun telah direncanakan. Oleh karena itu, ada beberapa agenda kerja yang perlu untuk dilakukan. Mengapa disebut sebagai agenda kerja dan bukan agenda riset, hal ini tentu berangkat dari satu pemahaman bahwa riset yang akan dikembangkan seyogyanya juga berangkat dari permasalahan yang ada di dalam tubuh militer Indonesia dan ditujukan bagi proses transformasi yang dikehendaki. Agenda kerja itu sendiri meliputi, agenda riset dan agenda praktis.
Agenda riset adalah tema-tema yang potensial untuk dikembangkan dalam studi militer dengan perspektif sosiologik, di antaranya, disertasi yang sedang disusun oleh penulis mengenai dinamika globalisasi dalam urusan militer serta transformasi institusi pendidikan militer. Dalam rencana disertasi tersebut akan dielaborasi sejauh mana globalisasi sebagai konteks yang melatari dinamika keamanan nasional negara-negara di dunia menuntut berbagai pihak terutama militer, untuk beradaptasi dan mempersiapkan antisipasi yang tidak saja bisa menanggulangi problem-problem globalisasi, namun juga bagaimana mengambil manfaat dari globalisasi. Selain dari riset seperti itu, masih terbuka kemungkinan bagi para sosiolog untuk juga membedah persoalan-persoalan lain di dalam tubuh militer yang berada pada level makro seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam tubuh TNI jika dikaitkan dengan semangat dan disiplin prajurit. Kemudian persoalan kepemimpinan yang ideal di dalam institusi militer, persoalan gender, kepemimpinan militer dalam ranah sipil serta para purnawirawan yang setelah tidak aktif dalam militer, kemudian kembali kepada masyarakat. Maupun persoalan-persoalan institusional yang ada di tubuh TNI seperti persoalan organisasi pendidikan di dalam TNI, persoalan interaksi sosial di atas geladak kapal perang yang harus berlayar sampai berbulan-bulan, atau kendala sosial para prajurit yang bertugas di wilayah-wilayah perbatasan yang terpencil dan lain-lain. Bahkan bisa menyentuh persoalan kesejahteraan keluarga-keluarga prajurit rendahan dan para perwira yang tidak memiliki jabatan struktural yang strategis. Serta problem-problem sosial lainnya yang menurut penulis akan sangat menarik untuk dikaji dengan kacamata sosiologis.
Sementara itu, agenda kerja yang lain adalah mendorong munculnya intelektual di dalam tubuh militer Indonesia sehingga dalam beberapa hal mereka juga bisa menyuarakan persoalan-persoalan yang ada di dalam institusi militer melalui bahasa akademik. Selain sebagai proses peningkatan kapasitas di dalam tubuh militer, hal ini juga bisa mendorong perdebatan akademis dengan “suara yang lain”. Perdebatan akademis dengan “suara yang lain” bukan dalam arti ingin mendikotomikan kembali sipil dengan militer, tetapi untuk mendapatkan pemaknaan yang lain karena jika yang berbicara mengenai institusi militer hanya dari kelompok-kelompok yang posisinya
185
bab7-8 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 185 7/10/12 2:41 PM

bukan anggota militer hal ini berpotensi memunculkan dominasi pemaknaan yang bukan tidak mungkin justru akan menghadirkan kembali dikotomi sipil-militer secara lebih ketat. Selain itu, membangun intelektual di dalam tubuh militer akan melahirkan generasi pemikir yang handal untuk mensosialisasikan gagasan dan idenya kepada dunia luar yang sedikit banyak akan menempatkan militer Indonesia menjadi institusi militer yang personelnya juga memiliki kemampuan untuk melakukan negosiasi dengan militer-militer negara lain ketika terjadi persoalan. Hemat penulis, kita semua sepakat bahwa militer Indonesia harus lebih kuat dan cerdas sehingga mampu menjawab tantangan dan ancaman nasional di masa depan yang jauh lebih kompleks.
7.6. Rangkuman
Secara sosiologis, Indonesia adalah konstruksi sosial yang telah berjalan seiring waktu yang cukup lama. Sebagai sebuah perjalanan ruang dan waktu, Indonesia mencerminkan sebuah peradaban yang sangat panjang. Sejarah telah mencatat bahwa sebagai sebuah identitas nasional, Indonesia kerap mengalami krisis maupun guncangan. Sebagai sebuah peradaban pula, Indonesia terus menerus berinteraksi dengan dunia luar. Interaksi yang tidak hanya menempatkan Indonesia sebagai obyek dari proses peradaban dunia, tetapi juga interaksi yang pada beberapa kurun waktu, Indonesia berhasil memberikan kontribusi gagasan yang diakui oleh dunia. Singkatnya menjadi subyek penting dari proses pem-beradaban dunia. Jika kita telisik lebih dalam, capaian itu bisa diperoleh karena di setiap moment itu, Indonesia bisa secara sadar menempatkan kemampuannya dalam setiap proses interaksi dengan dunia luar. Dalam konteks ini, Indonesia sebagai subyek dalam peradaban dunia adalah sebuah fakta historis.
Globalisasi yang dalam beberapa segi memproblematisir posisi dan peran negara di dalam masyarakat membuka ruang perdebatan yang seringkali mendorong satu konsepsi yang berhadap-hadapan (oposisi biner). Padahal dari pembahasan sebelumnya, globalisasi itu sendiri bisa dilihat sebagai sebuah paradoks. Di satu sisi merugikan, sementara di sisi yang lain bisa sangat menguntungkan. Terkait hal itu, dalam konteks Indonesia, diperlukan sebuah ikhtiar untuk tidak hanya mempelajari gagasan-gagasan globalisasi yang telah dikemukakan oleh banyak pemikir, tetapi juga sebuah upaya untuk bisa menyumbangkan pemaknaan dan pemahaman baru mengenai globalisasi yang “asli” Indonesia. Dalam level praktis, kita juga harus bisa mendorong para
186
bab7-8 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 186 7/10/12 2:41 PM

pemikir dan pengambil kebijakan untuk bisa menempatkan globalisasi secara lebih membumi. Atau bisa disebut, menempatkan globalisasi dalam konteks ke-Indonesia-an. Secara pragmatis pula, bisa dikatakan Indonesia mesti mampu mengambil sebanyak-banyaknya manfaat atas proses globalisasi dengan tetap menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan asing.
Dalam hal perkembangan institusi militer, globalisasi telah mendorong institusi manapun di dunia ini untuk bisa lebih inklusif agar dapat terus menjawab dinamika persoalan eksternal yang muncul. Sebagai sebuah pendekatan, sosiologi sebenarnya memiliki ruang yang cukup besar agar mampu menelaah lebih jauh institusi militer, dalam hal ini TNI. Menggunakan pendekatan sosiologik untuk menelisik institusi militer, tidak hanya memperkuat basis keilmuan dari sosiologi militer itu sendiri, tetapi secara institusional juga bisa mendorong institusi militer lebih adaptif dan antisipatif terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi. Pendekatan sosiologi sebagai upaya untuk melihat dimensi-dimensi sosial di dalam tubuh militer sesungguhnya adalah representasi dari sebuah upaya menemu-kenali nilai-nilai sipil di dalam militer itu sendiri. Dengan demikian, mengembangkan studi sosiologi militer dalam konteks Indonesia bisa kita maknai sebagai sebuah langkah untuk bisa mencairkan batas-batas psikologis dan politis dari dikotomi sipil-militer itu sendiri. Kiranya, itulah benang merah yang bisa dirangkum dari penjelasan mengenai kontribusi teoritik pada bagian ini.
Kendati bagian ini dinamakan “kontribusi teoritik”, penulis tidak hendak berpretensi bahwa apa yang telah dikemukakan di dalam bab ini bisa disandingkan dengan teori-teori mengenai globalisasi ataupun sosiologi militer yang telah mapan sebelumnya. Barangkali bagian ini lebih tepat untuk dikatakan sebagai satu upaya reflektif dari penulis untuk bisa memberikan sumbangan kecil terhadap gagasan mengenai globalisasi dan sosiologi militer itu sendiri. Tidak bisa dipungkiri bahwa latar sosial penulis sebagai seorang tentara aktif, memberikan sumbangsih pada konstruksi pemikiran yang terbangun di dalam buku ini. Dalam konteks ini pula, barangkali diri penulis bisa diibaratkan arena yang secara sosiologis menjadi tempat pertemuan antara ranah kajian sosiologi dengan konteks sosial penulis sebagai seorang perwira TNI AL. Dari arena itulah, substansi reflektif ini muncul.
187
bab7-8 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 187 7/10/12 2:41 PM

188
bab7-8 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 188 7/10/12 2:41 PM

Bab VIII
Penutup
189
bab7-8 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 189 7/10/12 2:41 PM

Bab VIII. PenutupHarus diakui dan diterima bahwa globalisasi adalah sebuah keniscayaan kontemporer. Tidak ada satu pun pihak yang bisa terbebas dari gelombang globalisasi meski ia berada di balik bukit yang paling pelosok atau mereka yang hidup dalam komunitas terasing dan primitif sekalipun. Globalisasi dalam berbagai wujud dan sifat dipenuhi kontradiksi dan paradoks yang bisa meniadakan maupun menghadirkan sesuatu. Globalisasi bisa menghidupkan yang pernah mati, bisa juga mematikan yang pernah hidup. Globalisasi bukan saja Westernisasi, dalam beberapa hal globalisasi juga men-dewesternisasi dengan memunculkan yang Eastern lebih banyak ke permukaan. Globalisasi tidak hanya bisa memaksa orang, kelompok masyarakat ataupun negara dalam bertindak, tapi tindakan orang, kelompok masyarakat dan negara juga memiliki peluang untuk bisa menahan, membelokkan ataupun mempercepat laju globalisasi itu sendiri.
Perkembangan dunia yang semakin terkoneksi satu sama lain telah memunculkan varian pemikiran mengenai gagasan keamanan nasional. Dalam dunia yang makin tanpa batas akibat globalisasi, persoalan keamanan akhirnya menyentuh esensi paling mendasar dari peradaban dunia, yakni manusia dan kemanusiaan. Namun demikian, dalam wujud yang paling kongkret, keamanan yang menjadi wacana penghubung yang paling sering muncul ketika kita berbicara mengenai persoalan globalisasi dan militer, negara dengan institusi militernyalah yang paling sering kita saksikan terlibat dalam proses interaksi, baik interaksi damai maupun konflik atau perang. Sehingga meski diskursus soal keamanan itu semakin hari semakin luas cakupan dan tingkatannya, kepentingan nasional tetap menjadi motif paling mendasar dari setiap argumentasi yang diungkapkan di dalam ranah keamanan.
Baik persoalan globalisasi maupun isu keamanan, keduanya mau tidak mau harus direspon secara baik oleh negara. Dalam hal ini, militer menjadi institusi paling bertanggung jawab dalam setiap persoalan yang mengganggu keamanan nasional suatu negara. Ketika persoalan globalisasi mewujud dalam berbagai bentuk dan kadar yang mengancam keamanan nasional, maka institusi militer diharapkan menjadi institusi yang mestinya paling depan dalam merespon ataupun mengadaptasi perubahan-perubahan yang terjadi. Tanpa adanya upaya untuk bisa mengikuti proses perubahan, yang berarti
190
bab7-8 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 190 7/10/12 2:41 PM

melakukan transformasi institusional, sebuah institusi militer bisa dipastikan akan berkurang kapasitasnya dalam merespon ancaman keamanan nasionalnya.
Selanjutnya, dalam melihat hubungan antara sipil dan militer, buku ini meskipun tidak secara khusus ditujukan untuk membahas persoalan itu, namun konsekuensi teoritiknya tetap tidak bisa dihindari. Salah satu masukan yang dianggap sangat berharga oleh penulis adalah ketimbang memproblematisasikan secara reproduktif persoalan sipil-militer, akan jauh lebih bermanfaat untuk melakukan pendekatan kepada institusi militer dari sudut pandang yang lebih sosiologik, yakni dengan mencoba memperluas cakupan kajian sosiologik dalam institusi militer, seperti persoalan relasi kekuasaan terkait dengan identitas (suku, agama dan ras) di dalam tubuh institusi militer, persoalan kelas sosial di dalam tubuh militer, persoalan gender dan kepemimpinan, persoalan pendidikan dan transformasi militer serta persoalan-persoalan sosiologis lainnya yang pasti akan lebih bermanfaat dalam upaya mencari benang merah yang bisa menggambarkan kesamaan-kesamaan institusi militer dengan institusi sosial lainnya. Singkatnya, masa depan ranah kajian sosiologi militer bisa secerah masa depan transformasi militer Indonesia jika hal ini dijadikan sebagai agenda kerja bersama, baik para sosiolog yang berada di kampus ataupun lembaga riset lainnya dan individu-individu di dalam tubuh militer yang memiliki kesadaran transformatif.
Akhirnya, secara sosiologis kita bisa katakan bahwa sumbangan terbesar teori-teori globalisasi terhadap kajian-kajian sosiologi militer adalah pembuktian bahwa institusi militer suatu negara sesungguhnya adalah institusi yang paling cepat bisa merespon proses perubahan atau paling adaptif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dalam lingkungan strategis mereka. Dengan pemahaman seperti ini, kiranya konsekuensi-konsekuensi lanjutan yang mungkin muncul dalam melihat hubungan antara sipil dan militer ataupun transformasi organisasional yang mungkin terjadi akan bisa ditelaah dari sudut pandang yang lebih mendekati kenyataan yang ada, ataupun dicarikan pola pendekatan yang akan bisa memberikan gambaran yang lebih realistis tentang hubungan sipil-militer yang ideal atau paling tidak yang diharapkan oleh masyarakat di masa depan.
191
bab7-8 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 191 7/10/12 2:41 PM

Daftar Pustaka
• Adamsky, Dima. 2010. The Culture of Military Inovation: the Impacts of Cultural Factors on the RMA in Rusia, the US and Israel. Stanford University Press. CA
• Avant, Deborah. 2006. “The Marketization of Security: Adventurous Defense, Institutional Malformation, and Conflict” dalam Jonathan Kirshner (ed): Globalization and National Security. Routledge, NY
• Ayoob, Mohammed, 2005, “Security in the Age of Globalization: Spearating Appearance from Reality” dalam: Ersel Aydinli and James N. Rosenau (ed) Globalization, Security and the Nation State: Paradigm in Transition. State University of New York
• Ayson, Robert. 2006. “The Future of National Security” dalam Robert G. Patnam (ed) Globalization and Conflict: National Security in a “New” Strategic Era. Routledge. NY
• Azizian, Rouben. 2006. “Russia, America and New Conflicts in Central Asia” dalam Robert G. Patnam (ed) Globalization and Conflict: National Security in a “New” Strategic Era. Routledge. NY
• Battersby, Paul and Joseph Ciracusa. 2009. Globalization and Human Security. Rowman and Littlefield Publisher. Maryland
• Blaker, James R. 2007. Transforming Military Force: The Legacy of Arthur Cebrowski and Network Centric Warfare. Praeger Security International
• Butler, R. 2010. “The US Shift Beyond Capital Asset” dalam Scott Jasper (ed). Transforming Defense Capabilities: New Approaches for International Security. Vivabooks
• Caforio, Giuseppe. 2003. Handbook of Sociology of the Military. New York: Kluwer Academic
• Chrisnandi, Yuddy. 2005. Reformasi TNI: Perspektif Baru Hubungan Sipil-Militer di Indonesia. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta
• Cribb, Robert. 2010. Para Jago dan Kaum Revolusioner Jakarta 1945-1949. Masup, Jakarta
• Dispenau. 2005. Sejarah Angkatan Udara Indonesia Jilid I-VII, Mabes TNI AU, Dinas Penerangan Angkatan Udara, Jakarta.
• Dombrowski, Peter. Eugene Gholz. 2006. Buying Military Transformation: technological Innovation and the Defense Industry. Columbia University Press
• Effendy, Muhadjir. 2008. Profesionalisme Militer: Profesionalisme TNI. UMM Press. Malang
• Fisher, Richard D. 2008. Cina”s Military Modernization. Greenwood Publishing Group
192
bab7-8 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 192 7/10/12 2:41 PM

• Gartska, John J. 2010. “Patterns in Inovation” dalam Scott Jasper (ed) Transforming Defense Capabilities: New Approach for International Security. Viva Books
• Giddens, Anthony. 2000. Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives. Routledge. NY
• Hayward, Anthony. 2006. “Humanitarian Intervention in East Timor: Some Ingredients for Building Sustainable Security” dalam Robert G.Patnam (ed) Globalization and Conflict: National Security in a “New” Strategic Era. Routledge. NY
• Headley, Jim. 2006. “Globalization and the “New War”: Case of Chechnya” dalam Robert G.Patnam (ed) Globalization and Conflict: National Security in a “New” Strategic Era. Routledge. NY
• Held, Anthony. Anthony McGrew. David Goldblatt. Jonathan Perraton. 1999. Global Transformation: Politics, Economics and Culture. Polity Press. Cambridge
• Huntington, Samuel. 1981. The Soldier and The State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations. Belknap Press, Harvard University
• Imran. Amrin, dkk., 1971. Sedjarah Perkembangan Angkatan-Darat, Seri Text-Book Sedjarah ABRI, Dephankam, Pusjarah ABRI, Jakarta
• Jasper, Scott. 2010. “The Capabilities Based Approach” dalam Scott Jasper (ed) Transforming Defense Capabilities: New Approach for International Security. Viva Books
• Jasper, Scott. 2010. “Measuring Progress” dalam Scott Jasper (ed) Transforming Defense Capabilities: New Approach for International Security. Viva Books
• Jojarth, Christine. 2009. Crime, War and Global Trafficking: Designing International Cooperation. Cambridge University Press
• Jones, Andrew. 2010. Globalization : Key Thinkers, Polity Press, UK• Kirshner, Jonathan. 2006. Globalization and National Security, Routledge, NY• Kirshner, Jonathan. 2006. “Globalization, Power, Prospect” dalam Jonathan Kirshner
(ed) Globalization and National Security. Routledge, NY • Mandeles, Mark D. 2007. Military Transformation Past and Present: Historical Lessons
for the 21st Century. Praeger Security International• Metz, Stephen. James Kievit. 1995. Strategy and Revolution in Military Police: From
Policy to Practice. Strategic Studies Institute, US. Army War College. PA• Mueler Karl.P. 2006. “The Paradox of Liberal Hegemony” dalam Jonathan Krishner (ed)
Globalization and National Security. Routledge, NY • Murray, Williamson. 1997. Thinking About Revolutions in Military Affairs. (diunduh dari
internet 12 Desember 2011)• Nasution, A.H. 1968. Tentara Nasional Indonesia, Seruling Masa, Jakarta.• Korten. David. 1995. When Corporation Rule The World. Kumarian Press.
193
bab7-8 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 193 7/10/12 2:41 PM

• Nel, Philip. 2006. Globalization and Violent Political Dissent in Developing Countries. Dalam Robert G. Patnam (ed) Globalization and Conflict: National Security in a “New” Strategic Era. (ed). Routledge. NY
• Ohmae, Kenichi. 1995. The End of the Nation-State: the Rise of Regional Economies. Simon and Schuster Inc. New York
• Osinga, Frans. Julian Lindley-French. 2010. “Leading Military Organization in the Risk Society: Mapping the New Strategis Complexity” dalam Joseph Soeters et al (ed) Managing Military Organization: Theory and Practice. Routledge
• Ouellet, Eric. 2005. Military Sociology. de Sitter Publications, Canada• Patnam, Robert.G. 2006. Globalization, the End of The Cold War and The Doctrine of
National Security. Dalam Robert G. Patnam (ed) Globalization and Conflict: National Security in a “New” Strategic Era. Routledge. NY
• Paul, TV. 2005. The National Security State and Global Terorism: Why The State Is Not Prepared for The New Kind of War. dalam James N. Rosenau and Ersel Aydinli (ed). Globalization, Security and the Naton State: Paradigm in Transition. State University of New York
• Piggot, Leane. 2006. Globalization, Power and Reform in The Middle East: Arab Response to September 11 and its Aftermath. dalam Robert G.Patnam (ed). Globalization and Conflict: National Security in a “New” Strategic Era. Routledge. NY
• Purwanto, Wawan. 2011. TNI dan Tata Dunia Baru Sistem Pertahanan. CMB Press. Jakarta
• Pusjarah TNI. Sejarah TNI Jilid I s.d. V, Markas Besar TNI, Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000, Jakarta.
• Ripsman, Norrin. T.V. Paul. 2010, Globalization and the National Security State, Oxford University Press
• Ritzer. G and D. J Goodman. 2003. Sociological Theory. New York: McGraw-Hill.• Rivai Ras, Abdul. 2001. Konflik Laut Cina Selatan, PT Rendino Putra Sejati, Jakarta• Saleh As”ad Djamhari. 1998. Ikhtisar Sejarah Perjuangan ABRI (1945-sekarang), Markas
Besar ABRI, Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, Jakarta.• Segal, Adam. 2006. Globalization Is a Double-Edge Sword: Globalization and Chines
National Security. dalam Jonathan Kirshner (ed) Globalization and National Security. Routledge, NY
• Shapiro, Robert J. 2008. Forecast: How Superpowers Populations and Globalization will
194
bab7-8 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 194 7/10/12 2:41 PM

Change the Way You Live and Work. St. martin Press. NY• Sloan, Elinor. 2008. Military Transformation and Modern Warfare: A Reference
handbook. Praeger Security International• Smith, Sir Ruppert. 2006. Requirements for Efective Military Interventions. dalam Robert
G.Patnam (ed) Globalization and Conflict: National Security in a “New” Strategic Era. Routledge. NY
• Smith, Michael E. 2010. International Security: Politics, Policy, Prospect. Palgrave Macmillan.NY
• Sorensen, George. 2005. Transformation and New Security Dillemas. dalam Ersel Aydinli and James N. Rosenau (ed). Globalization, Security and the Nation State: Paradigm in Transition. State University of New York
• Stulberg, Adam N. Michael D. Salomon. 2007. Managing Defense Transformation: Agency, Culture and Service Change. AshgatePublishing
• Sudono Jusuf. 1971. Sedjarah Perkembangan Angkatan Laut, Seri Text-Book Sedjarah ABRI, Dephankam, Pusjarah ABRI
• Sundhausen, Ulf. 1982. Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwifungsi ABRI. LP3ES. Jakarta
• Tabb, William K. 2009. Globalization Today: At The Borders of Class and State Theory. dalam Jerry Haris (ed).The Nation in the Global Era: Conflict and Transformation. Brill, Leiden
• Tim Benbow. 2004. The Magic Bullet ? Understanding the Revolution in Military Affair. Inggris: Brassey”s.
• Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, 2007. Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Jepang dan Zaman Republik (Edisi Pemutakhiran)-VI. Balai Pustaka. Jakarta
• Toffler, Alvin and Toffler, Heidi. 1980. The Third Wave. New York: William Morrow Co.Inc
• Trihadi. 1971. Sedjarah Perkembangan Angkatan Udara, Seri Text-Book Sedjarah ABRI, Dephankam, Pusjarah ABRI
• Uiterwijk, Daniel. Ivar Kappert. 2010. Research, Development and Innovation in the Military, dalam Joseph Soeters et al (ed) Managing Military Organization: theory and Practice. Routledge
195
bab7-8 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 195 7/10/12 2:41 PM

Internet
• http://analisisalutsista.blogspot.com/2011_08_04_archive.html”http://analisisalutsista.blogspot.com/2011_08_04_archive.html
• http://fleepzfloopz.blog.com/2011/05/10/posisi-indonesia-menangani-kejahatan-transnasional-dalam-kerangka-kerjasama-asean/”http://fleepzfloopz.blog.com/2011/05/10/posisi-indonesia-menangani-kejahatan-transnasional-dalam-kerangka-kerjasama-ASEAN/
• http://indo-defense.blogspot.com/”http://indo-defense.blogspot.com/• http://indo-defense.blogspot.com/2011/08/senjata-anti-tank-produksi-pindad-yang.html”http://
indo-defense.blogspot.com/2011/08/senjata-anti-tank-produksi-pindad-yang.html• http://indo-defense.blogspot.com/2011/09/new-york-idb-sebagai-negara-adidaya.html”http://
indo-defense.blogspot.com/2011/09/new-york-idb-sebagai-negara-adidaya.html • http://indo-defense.blogspot.com/2011/09/pemerintah-anggarkan-rp-99-t-untuk.html”http://
indo-defense.blogspot.com/2011/09/pemerintah-anggarkan-rp-99-t-untuk.html• http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/10/24/163892/18/KF-XIF-X-
Jet-Siluman-Buatan-Indonesia-Korsel”http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/10/24/163892/18/KF-XIF-X-Jet-Siluman-Buatan-Indonesia-Korsel
• http://teknologi.vivanews.com/news/read/246123-5-senjata-canggih-milik-as”http://teknologi.vivanews.com/news/read/246123-5-senjata-canggih-milik-as
• http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-setti/vasto-mundo/quem-batera-o-campeao-mundial-de-votos-o-presidente-da-indonesia-susilo-yudhoyono/
• http://www.globalfirepower.com/”http://www.globalfirepower.com/• http://www.indowebster.web.id/archive/index.php/t154497.html?s=bb0c8d979e32cd7eab6575
6fb7557bba” http://www.indowebster.web.id/archive/index.php/t154497.html?s=bb0c8d979e32cd7eab65756fb7557bba
• http://www.unodc.org”http://www.unodc.org• http://www.globalissues.org/issue/73/arms-trade-a-major-cause-of-suffering”www.
globalissues.org/issue/73/arms-trade-a-major-cause-of-suffering• http://www.crs.gov. Emma Chanlett-Avery, Specialist in Asian Affairs, 18 January 2011.
Congressional Research Service.• http://www.mindef.gov.sg/content/imidef/publications/pointer/journals/2004/v30n1/features/
feature4.html. Tim Huxley, Senior Fellow for Asi-Pasific Security at the International Institute for Strategic Studies, Defending the Lion City: The Armed Forces of Singapore.
• http://www.idsa.in/jds/2 2 2008 RMAandIndiaMilitaryTransformation VKKapoor. V.K. Kapoor .RMA and India’s Military Transformation.Journal of Defence Studies Vol. 2 No.2. 2008.
• http://news.xinhuanet.com/english2010/Cina/2011-03/31/c 13806851
196
bab7-8 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 196 7/10/12 2:41 PM

ABRI
Disintegrasi, 129, 150
Dwifungsi, 16
Hankamnas, 130, 151
Markas Besar, 151
Netralitas, 135
Organisasi, 129, 130, 131, 132
Pemilu, 135
Reformasi, 133, 134
Renstra Bangkuat, 131
Rivalitas, 129
Sospol, 16, 97, 134
Adamsky, Dima, 106
Afghanistan, 56, 73, 77, 94, 98, 99, 137, 158
Afrika, 8, 10, 44, 64, 72, 74, 158
Barat, 77, 78
Selatan, 29, 174
Sub-Sahara, 45
Timur, 77, 78
Agenda
Kerja, 185, 191
Agen-struktur, 21, 31
Ahtisaari, Martti, 142
Alutsista, 62, 65, 80, 106, 139, 147
Amerika Latin/Selatan, 44, 64, 77, 78, 158
Amerika Serikat (AS), 6, 8, 9, 19, 23, 66,
101, 106
Departemen Pertahanan, 106
Joint Vision, 106
Krisis, 157, 158, 161
QDR, 106
Indeks
Angkatan Darat (AD), 60, 61, 92, 125, 127,
128, 129
Angkatan Laut (AL), 7, 60, 61, 90, 125,
126, 129, 144
Angkatan Pemuda Indonesia (API), 120
Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI),
126, 127
Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat
(APRIS), 126
Angkatan Udara (AU), 60, 61, 65, 68, 90, 108,
125, 126, 129
Arab Saudi, 64, 65
ASEAN, 62, 75, 76, 77, 78, 79
KTT, 77
Asia, 23, 27, 32, 64, 72, 74, 78
Pasifik, 95
Tenggara, 44, 77, 78, 79, 95, 96, 103,
136, 140
Australia, 59, 69, 79, 97, 98, 99, 100, 101, 107
Austria, 72
Aydinli, Ersel, 19
Ayoob, Mohammad, 18
Azizian, Rouben, 69
Badan Keamanan Rakyat (BKR), 119, 120,
122, 123, 143, 144, 145
Badan Pembantu Prajurit/Pembelaan (BPP), 119
Bali, 19, 126, 172
Bangkok, 77
Basque, 45
Belgia, 72, 137
197
bab7-8 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 197 7/10/12 2:41 PM

Benbow, Tim, 58
Birokrasi, 16, 26, 61, 179
Brazil 181, 182
Brunei Darussalam, 77, 139
Bundeshwer, 90
Bunker, Ellswoth, 139
Burma, 136
Bush, George W, 94, 107, 141, 182,
Butler, R, 106, 107
Caforio, Giuseppe, 29, 49, 175
Castells, Manuel, 6
Cebrowski, Arthur, 107, 108
Chretein, Jean, 89, 90
Cina, 8, 9, 10, 23, 27, 33, 44, 56, 64, 65, 66,
68, 72, 73
Partai Komunis Cina (PKC), 102, 103, 106
People Liberation Army (PLA), 102, 105
Pertahanan Nasional, 103, 104, 114
Civil Society, 69, 133
Clausewitz, Von, 86
Clausewitzian, 43, 44
Clinton, Bill, 93, 182
Crouch, Harold, 184
Dataran Tinggi Golan, 93
Declaration of ASEAN concord, 77
Demokrasi, 7, 8, 17, 18, 92, 167, 179, 181, 182
Departemen Pertahanan Keamanan
(Dephankam), 130, 131
Deregulasi, 32
Desentralisasi, 61, 168
Dilthey, 30
Djuanda, 127, 128
Eisenhower, Dwight, 93
Ekonomi
Internasional, 35
Nasional, 165, 166
Polarisasi, 35, 159
Politik, 17, 19, 20, 22, 32, 35, 44, 55, 69,
71, 72, 73, 81, 101, 102, 114
Regional, 33
Elite, 6, 129, 176
Eropa, 64, 73, 74, 89, 90, 155, 157, 158,
161, 162
Faulks, Keith, 34, 35, 36, 49
Filipina, 79
Fisher, Richard D, 102
Fitzsimmons, Dan, 89
Futenma, 94
G-20, 161
Geopolitik, 20, 96
Gerakan Aceh Merdeka (GAM), 141, 142
Gerakan Non Blok (GNB), 137
Giddens, Antony, 21, 26, 27, 49, 56, 101, 148,
161, 167, 172, 173
manufactured risk, 26
Refleksifitas, 27
Restrukturisasi, 27
Risiko, 27
Ruang dan Waktu, 26, 27, 172, 173
Strukturasi, 28, 148
Globalisasi
Ekonomi, 34, 35, 40
Fundamentalisme, 27, 172, 177
Konflik, 19
Kosmopolitanisme, 27, 172, 177
Neo liberalisasi, 36
198
bab7-8 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 198 7/10/12 2:41 PM

Oposisi biner, 186
Paradoks, 36, 44, 56, 157, 163, 186, 191
Sosiologi, 156
Westernisasi, 8, 172, 190
Glokalisasi, 27
Guam Doctrine, 93
Guangzhou, 33
HAM, 73, 107
Pelanggaran, 140, 151
Hamengkubuwono IX, Sri Sultan, 121, 126
Hashimoto, Ryutaro, 93
Hatoyama, Yukio, 94
Hatta, Moh, 126
Hegemoni, 27, 73
Heiho, 119, 120
Kaigun, 120
Hidayat, 125, 127
Hungaria, 72
Huntington, Samuel, 29, 30, 174, 178, 179, 183
India, 8, 9, 65, 66, 95, 98, 99, 100
Indonesia, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 20, 21, 23,
49, 51, 54, 62, 63, 67, 73, 74, 76, 78, 79, 83,
97, 102, 109, 114, 118, 127, 131, 133, 135,
136, 137, 138, 139, 141, 147, 148, 157, 159,
161, 162, 163, 165, 166, 167,172, 173, 174,
179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186,
187, 191
Inggris, 8, 45, 60, 64, 72, 89,92, 99, 109, 135,
136, 137, 138, 140
Internasionalisasi, 34, 35, 172
Irak, 8, 56, 66, 73, 94, 98, 99, 157
Iran, 8, 68, 77
Iskandar, holand, 124
Islam, 8, 9, 45, 73
Israel, 8, 73, 74, 99, 138
Italia, 26, 64, 142
Janowitz, Morris, 29, 30, 31, 174, 177
Jepang, 34, 64, 72, 79, 80, 92, 93, 94, 95, 112,
119, 120, 121, 135, 136, 145, 147
Jerman, 64, 72, 89, 90, 91, 109
Kamboja, 74, 77, 78,93
Kan, Naoto, 94
Kanada, 84, 89, 90, 107, 108, 109, 173
Kant, Immanuel, 30
Kapitalisme, 8, 26, 49, 72, 80, 113, 155, 156,
157, 161
Kargil, 100
Kartakusuma, M.M.R, 129
Kartasasmita, Didi, 124
Kartawinata, Aruji, 120
Keamanan
Ancaman, 17, 19, 82, 166, 173,
178, 191
Global, 17, 18, 21, 75, 81, 165
Internasional, 18, 21, 47, 54, 103, 173, 182
Konsepsi, 18, 155
Nasional, 18, 19, 20, 22, 23, 28, 37, 38, 40,
41, 42, 43, 48, 54, 55, 56, 57, 62, 68, 69, 80,
81, 82, 86, 87, 102, 107, 112, 114, 127, 154,
157, 160, 161, 163, 164, 166, 167, 168, 173,
175, 177, 178, 182, 185, 186, 187, 190, 191
Regional, 18, 33, 43, 44, 45, 48,97, 155
Studi, 17
Swasta, 109, 155
199
bab7-8 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 199 7/10/12 2:41 PM

Kearifan Lokal, 35
Kejahatan Lintas Negara, 75, 76, 77, 78, 79,
80, 81, 88
Kepinevich, Andrew, 57, 58
Kepulauan Spratly, 74, 142
Ki-Moon, Ban, 75
KNIL, 121, 126, 143, 147
Koizumi, Junichiro, 94, 95
Komando Daerah AL (Kodaeral), 131
Komando Operasi Tertinggi (KOTI), 128, 129
Komando Utama (Kotama), 130, 131, 132
Komite Nasional Indonesia (KNI), 119, 143
komunis, 72, 92, 142, 144, 163
Konferensi Meja Bundar (KMB), 137, 139
Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika, 137
Konflik
Antar Negara, 9, 43, 44, 69, 74, 82
Pola, 19, 69, 70, 71, 81
Kontestasi, 160, 161
Korea Selatan, 79, 95, 141
Korea Utara, 93
Krepinevich, Andrew, 58
Krishner, Jonathan, 37, 38, 49, 173
Kuala Lumpur, 77
Laos, 77
Laut Cina Selatan, 74, 77, 78, 103, 104
Laut Hitam, 77, 78
Laut Mediterania, 78
Lindemann, Thomas, 86
Lombard, Denys, 9
London, 19, 138
M.V. Sinar Kudus, 83
Madrid, 19
Maguwo, 123
Malaysia, 10, 74, 77, 78, 96, 139, 142, 181
Konfrontasi, 139, 150
Sipadan - Ligitan, 142
Manila, 78, 79, 139
Marshall, Andrew, 100
Martin, Paul, 89
Masyarakat Sipil, 20, 29, 30, 36, 54, 60, 114,
174, 175, 176, 177,
Mesir, 137, 138
Military Technical Revolution (MTR), 80, 156,
Militer
Adaptasi, 29, 58, 60, 61, 98, 118, 174, 177,
185, 190
Belanja, 43, 64, 65
Doktrin, 43, 59, 60, 91, 108, 166
Dominasi, 21
Gender, 49, 185, 191
Humanisme, 164
Industri, 99, 101, 102, 105, 106, 112,
113, 157
Infrastruktur, 42, 97
Inklusif, 168, 184, 187
Institusi, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 28, 29, 30,
49, 50, 51, 54, 81, 89, 90, 92, 101, 102, 103,
106, 109, 112, 113, 114, 118, 143, 147, 154,
157, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168,
174, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 185,
186, 187, 191
Kajian, 172, 175
Kapasitas, 63, 173, 176, 181, 185
Kelas Sosial, 191
Kepemimpinan, 99, 173, 176, 179, 181, 185,
200
bab7-8 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 200 7/10/12 2:41 PM

Operasi, 7, 10, 61,65, 73, 80, 83, 90, 94, 98,
99, 100
Organisasi, 16, 18, 19, 29, 59, 60, 61, 62, 89,
96, 100, 123, 124, 127, 144, 173, 174,
175, 177
Pendidikan, 105, 147, 185
Peran, 16, 17, 41, 89
Relasi Sipil, 21, 29, 30, 50, 51, 114, 151,
163, 164, 166, 174, 175, 177, 179, 180, 181,
182, 183, 187, 191
Struktur Sosial, 21, 50
Teknologi, 22, 62, 68, 106, 108, 158,
166, 176
Wajib, 43, 59, 98
Wilayah, 105
Modernisasi
juggernaut, 27, 160
Realisasi, 27
Moefreini, 120
Mozambik, 93
multistate centric, 20, 37, 82, 83
Mustopo, 124
Myanmar, 77, 78, 133
Napoleon, 58, 59
Narkoba, 75, 76, 77
Nasser, Gamal Abdul, 137, 138
Nasution, A.H, 11, 16, 125, 126
NATO, 90, 91, 95, 173
natural economic zone, 33
negara kawasan, 33, 34, 83
Nehru, Jawaharlal, 137
Network society, 6
NICA, 121, 136
Nixon, Richard, 93, 182
Nkrumah, Kwame, 137
Nobusuke, Kishi, 93
Obama, Barack, 94, 181, 182
Ohio, 68
Ohmae, Kenichi, 31, 32, 33, 34, 40, 49
Operasi Parakram, 100
Orde Baru, 16, 114, 147, 179, 180, 184
Organisasi Sosial, 17, 20, 174, 177
Otoritas Sipil, 20, 113, 114, 164, 166, 168, 179
Ouellet, Eric, 29, 30, 31, 49, 175
Owens, William A, 100
Pakistan, 56, 65, 77, 100, 157
Palestina, 8, 73, 74
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(PPKI), 119
Paracel, 74, 142
Paradigma Peperangan, 43, 86
Pardi, M, 144
Paris, 138
Partai Aksi Rakyat, 95
Partai Nasional Indonesia (PNI), 119
Patnam, Robert G, 69
Paul, T.V, 40, 42, 45, 48, 49, 155, 167, 174
PBB, 10, 11, 75, 78, 79,94, 136, 137, 138, 139,
140, 148
Pembangunan Nasional, 131, 132, 140, 161, 162
Pembela Tanah Air (PETA), 119, 120, 126, 147
Penjaga Keamanan Rakyat (PKR), 120
Pentagon, 19, 73, 107
Peperangan Generasi, 87, 88, 156, 164
Perancis, 58, 59, 64, 72, 99, 109, 138, 157
Perang
201
bab7-8 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 201 7/10/12 2:41 PM

Arab, 138, 148
Dingin, 9, 16, 19, 22, 31, 33, 42, 45, 54, 57,
69, 70, 72, 73, 74, 80, 91, 93
Dunia Kedua, 16, 29, 70, 72, 92, 94, 148
Dunia Pertama, 70, 72
Eskalasi, 44, 69
Kosovo, 66
Salib, 88
Sipil, 88
Teluk, 59, 93, 107
Yunani Kuno, 88
Perry, William J, 100
Persia, 93
Perubahan Iklim, 28, 173
Piggot, Leane, 69
Plato, 50
Polri, 127, 128, 131, 132, 133, 134
Proteksi, 32
PT. Pindad, 67
Pugh, Michael, 182, 183
Putin, Vladimir, 66, 182
Rahmad Darmawan (RD), 181
Restrukturisasi, 27, 146, 177
Revolusi
Agraris, 8
Doktrin, 60, 61
Industri, 8, 38, 59
Perang, 58
Teknologi, 59, 60, 61
Revolutionary in Military Affairs (RMA),
22, 42, 54, 57, 58, 59, 60, 62, 80, 81, 82, 87,
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 108,
109, 112, 156, 166, 175
Rice, Condoleezza, 141
Rikugun Koku Butai, 120
Ripsman, Norrin, 40, 42, 45, 46, 48, 49, 55,
167, 174
Ritzer, George, 26, 56
Roosseno, 124
Rosecrance, Richard, 41
Rukavishnikov, Vladimir O, 182, 183
Rumania, 72
Rumsfield, Donald, 107, 108
Rusia, 44, 64, 66, 72, 74, 79, 89, 91, 92, 99, 103,
112, 113, 140, 141, 158
Salomone, Michael D, 92
Samudera Hindia, 77, 78, 94
San Francisco Peace Treaty, 92
Sato, Eisaku, 93
Sekutu, 72, 93, 109, 112, 119, 121, 135, 136,
138, 158
Selandia Baru, 80, 140
Selat
Malaka, 77, 78
Taiwan, 93
Self-Defense Forces (SDF), 92, 93, 94
Semenanjung
Korea, 103, 104
Sinai, 138
Shutoken, 34
Simatupang, T.B, 124, 126
Singapura, 78, 95, 96, 97, 98, 112, 140
Singh, Bilver, 184
Sloan, Elinor, 59, 103, 106, 107, 108, 109
202
bab7-8 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 202 7/10/12 2:41 PM

Soedirman, 121, 122, 125, 126, 127, 136, 144
Soeharto, 129, 147
Soekarno, 120, 127, 128, 129, 137, 138, 139,
146, 147
Soeljoadikusumo, Muhammad, 121
Soemahardjo, Oerip, 121, 122, 124, 143, 144
Soeprijadi, 121
Soerahmad, R, 120
Somalia, 83, 157
Sosiologi
Agama, 29, 175
Gender, 29, 175
Militer, 7, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 29,
30, 49, 174, 175, 176, 184, 187, 191
Pendidikan, 29, 175
Steinhoff, Dirk, 90
structural adjustment
IMF/World Bank, 40
Stulberg, Adam N, 92
Sudan Selatan, 74
Sundhausen, Ulf, 176, 184
Sunjoyo, 124
Supomo, 124
Suryadarma, 124, 126, 144, 145
Sutirto, 124
Swedia, 68
Taiwan, 56, 103, 104, 105
Tan, Andrew, 98
Tel Aviv, 138
Tentara Keamanan Rakyat (TKR), 121,122, 123,
124, 143, 144, 145
Tentara Laut Republik Indonesia (TLRI), 144
Terorisme, 7, 19, 27, 40, 42, 43, 45, 56, 70, 73,
75, 76, 79, 81, 88, 99, 107, 157, 164, 165,
172, 173
Thailand, 74, 77, 78
Timor Leste, 73, 141
Timor Timur, 93, 140, 141
Timur Tengah, 10, 44, 74
Tito, Josip Broz, 137
TNI
Kesejahteraan, 180, 185
Organisasi, 23, 127, 132, 143, 144, 145
Pertarungan Konsep, 126, 149
Politik Praktis, 135, 163
Rasionalisasi, 119, 143
Reformasi, 163, 164
Reorganisasi, 127, 128, 129, 143
Sejarah, 124, 133
Transformasi, 7, 154, 166, 168
Toffler, Alvin, 58, 59
Toffler, Heidi, 58, 59
traditional state-centric, 20, 37
Trafficking, 78, 79
Transformasi Militer, 22, 23, 62, 80, 81, 86, 89,
90, 91, 92, 97, 99, 100, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 156, 157,
163, 165, 175
Amerika Serikat (AS), 80, 106, 108, 109
Cina, 101, 102, 104, 105, 114
India, 99, 100
Indonesia, 10, 22, 114, 165, 166, 191
Inggris, 92
Jepang, 92
Jerman, 90
203
bab7-8 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 203 7/10/12 2:41 PM

Kanada, 89
Rusia, 91
Singapura, 95, 96, 98
Transnational Organized Crimes (TOC), 75, 80
Turki, 8
Ufimtsev, Pyotr, 66
Uni Sovyet, 9, 57, 66, 69, 72, 80, 92, 93, 103,
112, 137, 138, 139, 147, 157
Vietnam, 93, 140, 142
Wall Street, 157
Weber, Max, 30
Wiranto, 133
WTC, 19, 55, 73, 107
11 September 2001, 44, 45, 55, 69, 70, 73,
88, 89, 97, 107, 108
Xiaoping, Deng, 104
Yamin, Moh, 127
Yudhoyono, Susilo Bambang (SBY),
16, 141, 181
Yugoslavia, 72, 137
Zacher, Mark, 41
204
bab7-8 M&G_Cetakan ke2-M5.indd 204 7/10/12 2:41 PM