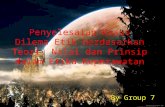Pembahasan kasus
-
Upload
igustibagusadhista -
Category
Documents
-
view
224 -
download
2
description
Transcript of Pembahasan kasus

Pembahasan
The NationalKidney Foundation- Kidney Dialysis Outcome Quality Iniatiative
(NKF-K/DOQI) mendefinisikan CKD sebagai (1) kerusakan ginjal yang terjadi selama tiga bulan atau lebih, berupa kelainan struktural atau fungsional ginjal, dengan atau tanpa penurunan laju filtrasi glomerulus (LFG), dengan manifestasi kelainan patologis atau petanda (marker) kerusakan ginjal , termasuk kelainan dalam komposisi darah maupun urin, atau kelainan dalam tes pencitraan ; atau (2) LFG < 60 ml/menit/1,73m2 selama tiga bulan atau lebih, dengan atau tanpa kerusakan ginjal. Berdasarkan derajat penyakit, yang ditentukan dari nilai laju filtrasi glomerulus, maka NKF-K/DOQI merekomendasikan klasifikasi CKD menjadi 5 stadium. Menurut klasifikasi ini, CKD stage V ditegakkan bila nilai LFG < 15 ml/menit/1,73 m2.3
Gejala klinik yang ditunjukkan oleh penderita CKD meliputi: (1) sesuai dengan penyakit yang mendasari seperti diabetes melitus, infeksi traktus urinarius, batu traktus urinarius, hipertensi, hiperurisemi, Lupus Eritematosus Sistemik dan lain sebagainya. (2) gejala-gejala Sindrom uremia, yang terdiri dari lemah, letargi, anoreksia, mual muntah, nokturia, kelebihan volume cairan (volume overloaded), neuropati perifer, pruritus, uremic frost, perikarditis, kejang-kejang sampai koma. (3) Gejala komplikasinya antara lain, hipertensi, anemia, osteodistrofi renal, payah jantung, asidosis metabolik, gangguan keseimbangan eletrolit (sodium, kalium, klorida).4
Dalam kepustakaan disebutkan bahwa penyebab gagal ginjal yang menjalani hemodialisis di Indonesia th. 2000 meliputi: Glomerulonefritis (46,39%), Diabetes melitus (18,65%), Obstruksi dan infeksi (12,85%), Hipertensi (8,46%), Sebab lain (13,65%).4
Pasien juga mempunyai riwayat hipertensi sejak 5 tahun yang lalu, dan telah mendapatkan pengobatan captopril 2 x 1 tablet sehari. Akan tetapi pasien tidak rutin minum obat. Riwayat penyakit lain seperti diabetes melitus, penyakit jantung serta asma disangkal, demikian pula tidak ada riwayat trauma pada kedua ginjal.
Gambaran laboratorium CKD meliputi: (1) sesuai dengan penyakit yang mendasarinya; (2) penurunan fungsi ginjal berupa peningkatan kadar ureum dan kreatinin serum serta penurunan LFG yang dihitung mempergunakan rumus Kockcroft-Gault; (3) kelainan biokimiawi darah meliputi penurunan kadar hemoglobin (anemia), peningkatan kadar asam urat, hiper atau hipokalemia, hiponatremia, hiper atau hipokloremia, hiperfosfatemia, hipokalsemia, asidosis metabolik dan (4) kelainan urinalisis yang meliputi proteinuria, hematuria, leukosuria, cast, isostenuria.4
Dari hasil pemeriksaan darah lengkap pada kasu ini, dijumpai adanya anemia ringan normokromik normositer (hemoglobin 9,40 g/dl, MCV 91,50 fL, MCH 27,70 Pg) dan trombositopenia (126,40 x 103/μL). Pada pemeriksaan kimia klinik ditemukan adanya peningkatan kadar BUN (88 mg/dl), peningkatan kreatinin (16,63 mg/dl) dan penurunan LFG (5,03 ml/menit/1,73 m2). Pada pemeriksaan analisis gas darah ditemukan adanya asidosis metabolik terkompensasi parsial (pH 7,32, PCO2 21,00 mmHg, PO2 147,00 mmHg, HCO3 10,60 mmol/L, BEecf -15,30 mmol/L) dan hiponatremia (136,00 mmol/L). Pada pemeriksaan urinalisis ditemukan leukosuria (25,00 Leu/uL), proteinuria (500,00 mg/dl), glukosuria (50,00 mg/dl) dan haematuria (150,00 Ery/uL).
Pemeriksaan radiologis pada CKD meliputi foto polos abdomen, pielografi intravena, ultrasonografi, serta renografi. Pada foto polos abdomen bisa tampak adanya batu radioopak. Pielografi intravena jarang dikerjakan, karena kontras sering tidak bisa melewati filter glomerulus, disamping

kekhawatiran terjadinya pengaruh toksik oleh kontras terhadap ginjal yang sudah mengalami kerusakan. Pielografi antegrad atau retrograd dilakukan sesuai dengan indikasi. Ultrasonografi ginjal bisa memperlihatkan ukuran ginjal yang mengecil, korteks yang menipis, adanya hidronefrosis atau batu ginjal, kista, massa, kalsifikasi. Sedangkan pemeriksaan pemindaian ginjal atau renografi dikerjakan bila ada indikasi.4
Pada kasus ini, telah dilakukan pemeriksaan foto polos (BOF) abdomen dan didapatkan kesan adanya batu radiopaque di ureter kiri 1/3 distal, dan batu radiopaque di buli-buli. Untuk mendapatkan pencitraan ginjal yang lebih spesifik, maka pada pasien ini juga direncanakan pemeriksaan ultrasonografi abdomen. Pada pasien juga dilakukan pemeriksaan foto thorax AP, dan didapatkan kesan adanya kardiomegali dengan edema pulmonum.
Berdasarkan hasil anamnesis, pemeriksaan fisik dan penunjang, maka pasien ini didiagnosis dengan CKD Stage V karena secara klinis dijumpai 3 gejala/tanda klasik CKD yaitu edema, anemia, dan hipertensi, ditambah penurunan fungsi ginjal yang ditandai dengan LFG < 15 ml/menit/1,73m2. Kausa PNC dipilih karena pasien memiliki riwayat batu saluran kencing yang dikuatkan oleh bukti radiologis.
Penatalaksanaan CKD meliputi: (1) terapi spesifik terhadap penyakit dasarnya, (2) pencegahan dan terapi terhadap kondisi komorbid (faktor komorbid tersebut antara lain gangguan keseimbangan cairan, hipertensi yang tidak terkontrol, infeksi traktus urinarius, obat-obat nefrotoksik, bahan radiokontras atau peningkatan aktivitas penyakit dasarnya), (3) memperlambat perburukan fungsi ginjal (restriksi protein dan terapi farmakologis),(4) pencegahan dan terapi terhadap penyakit kardiovaskular (pengendalian diabetes, hipertensi, dislipidemia, anemia, hiperfosfatemia, dan terapi terhadap kelebihan cairan dan gangguan
keseimbangan elektrolit), (5) pencegahan dan terapi terhadap komplikasi (anemia, osteodistrofi renal, pembatasan cairan dan elektrolit) dan (6) terapi pengganti ginjal berupa dialisis atau transplantasi ginjal.4
Terapi pengganti ginjal merupakan terapi definitif pada CKD stadium V. Terapi pengganti ginjal tersebut dapat berupa hemodialisis, peritoneal dialisis, dan transplantasi ginjal. Hemodialisis emergensi adalah salah satu pilihan hemodialisis yang dikerjakan pada pasien-pasien CKD dengan LFG < 5 ml/menit/1,73 m2 dan atau bila ditemukan salah satu dari keadaan berikut: (1) adanya keadaan umum yang buruk dan kondisi klinis yang nyata, (2) serum kalium > 6 meq/L, (3) ureum darah > 200 mg/dL,(4) pH darah < 7,1, (5) anuria berkepanjangan (> 5 hari), (6) serta adanya bukti fluid overload.4
Pada kasus ini, karena pasien menderita CKD stage V, maka telah terjadi kegagalan fungsi ginjal yang didukung dengan GFR 5,03 mL/min/1,73 m2. Sehingga penatalaksanaan utama pada pasien ini ialah terapi pengganti ginjal berupa hemodialisis. Hemodialisis emergensi dipilih pada pasien ini karena dijumpai adanya uremic lung yang merupakan salah satu petanda terjadinya fluid overload. Selanjutnya pasien menjalani Hemodialisis regular 2x seminggu.
Disamping itu pada pasien ini juga diberikan beberapa terapi penunjang lainnya, yang disesuaikan dengan keadaan klinis pasien, meliputi: IVFD NaCl 0,9% 8 tpm, captopril 3 x 50 mg, amlodipine 1 x 10 mg, asam folat 2 x 2 mg, CaCO3 3x500 mg , transfusi PRC hingga Hb ≥ 10 gr/dL, diet tinggi kalori 35 kkal/kgBB/hari (2450 kkal/hari), rendah protein 0,8 gr/kgBB/hari (56 gram/hari), rendah garam 100 mEq/hari (230 mg/hari). Adapun dasar pemberian terapi tambahan tersebut akan dijelaskan dalam pembahasan selanjutnya.
Anemia terjadi pada 80-90% pasien CKD. Mekanisme terjadinya anemia pada CKD

terutama disebabkan oleh defisiensi eritropoetin akibat menurunnya fungsi ginjal. Hal-hal yang lain yang ikut berperan dalam terjadinya anemia adalah: defisiensi besi, kehilangan darah (misalnya akibat perdarahan saluran cerna atau hematuria), massa hidup eritrosit yang pendek akibat terjadinya hemolisis, defisiensi asam folat, penekanan sumsum tulang oleh substansi uremik, proses inflamasi akut maupun kronik. Evaluasi terhadap anemia dimulai saat kadar hemoglobin ≤ 10 gr % atau HCT ≤ 30% yang meliputi evaluasi terhadap status besi (SI/TIBC/ferritin), mencari sumber perdarahan, morfologi eritrosit, serta kemungkinan adanya hemolisis.4
Pada kasus ini, pasien mengalami anemia ringan normokromik normositer (Hb 9,40 gr/dL, HCT 31,20%, MCH 27,70fl, MCV 91,50pg). Penyebab anemia masih ditelusuri, dimana salah satu pemeriksaan penunjang yang direncanakan ialah pemeriksaan status besi (SI/TIBC/serum ferritin) untuk menyingkirkan kemungkinan defisiensi besi sebagai penyebab anemia pada pasien ini
Koreksi anemia pada penderita CKD dimulai pada kadar Hemoglobin < 10 gr/dL dengan target terapi, tercapainya kadar hemoglobin antara 11-12 gr/dL. Pemberian tranfusi pada CKD harus dilakukan dengan hati-hati, berdasarkan indikasi yang tepat dan pemantauan yang cermat. Tranfusi darah yang dilakukan secara tidak cermat dapat mengakibatkan kelebihan cairan tubuh dan hyperkalemia yang kita ketahui menyebabkan perburukan fungsi ginjal.4
Pada pasien ini, dilakukan tranfusi Packed Red Cells (PRC) sebanyak 2 kolf. Masing-masing 1 kolf tiap kali menjalani hemodialisis (pasien sudah menjalani 2x Hemodialisis). Setelah mendapatkan 2 kali tranfusi terjadi kenaikan kadar hemoglobin sesuai target yang diharapkan.
Hipertensi merupakan salah satu temuan klinis lain yang juga sering dijumpai pada
CKD. 3
Pada kasus ini, pasien didapatkan dengan hipertensi grade II dan riwayat pengobatan captopril 2 x 25 mg, namun hipertensinya masih belum terkontrol.
Kontrol terhadap tekanan darah sangat penting, tidak hanya untuk menghambat perburukan CKD, tetapi juga untuk mengurangi risiko penyakit kardiovaskuler. Penatalaksanaan hipertensi pada pasien CKD berupa diet rendah garam dan pemberian obat antihipertensi golongan ACE inhibitor dan atau Angiotensin Receptor Blocker (ARB). ACE inhibitor dan ARB merupakan pilihan obat antihipertensi untuk pasien CKD karena keduanya mengurangi hipertensi glomerulus melalui 2 mekanisme, yaitu: (1) menurunkan tekanan darah sistemik dan menyebabkan vasodilatasi arteriol eferen; dan (2) meningkatkan permeabilitas membran glomerulus dan menurunkan produksi sitokin fibrogenik. ARB mempunyai efek samping yang lebih sedikit dibandingkan ACE inhibitor (seperti batuk atau hiperkalemia), akan tetapi karena harga ARB lebih mahal, maka biasanya ARB direkomendasikan bagi pasien yang tidak memberikan respon positif terhadap pengobatan dengan ACE inhibitor.3
Adapun target penurunan tekanan darah yang ingin dicapai pada pasien CKD, tergantung pada kadar protein dalam urin pasien. Pada pasien dengan kadar protein urin > 1 gr/hari, target tekanan darah yang diinginkan ialah < 125/75 mmHg, sedangkan bila kadar protein dalam urin < 1 gr/hari, target penurunan tekanan darah yang diharapkan ialah < 130/80 mmHg.3
Pada pasien ini, diberikan pengobatan berupa Captopril 3 x 25 mg yang dikombinasikan dengan amlodipine 1 x 10 mg. Pengkombinasian ACE inhibitor dengan Calcium Channel Blocker pada pasien ini dilakukan karena pasien juga dicurigai mengalami penyakit jantung hipertensi, yang didasarkan adanya gambaran kardiomegali pada pemeriksaan foto thorax.

Salah satu manifestasi klinis yang sering dijumpai pada penderita CKD ialah edema paru. Berdasarkan mekanisme yang mendasarinya, edema paru pada pasien dengan penyakit ginjal secara umum dibedakan menjadi: (1) edema paru renal primer dan (2) edema paru sekunder sebagai konsekuensi renal dan jantung. Edema paru renal secara klasik berkaitan dengan adanya kelebihan volume cairan ekstraseluler sebagai akibat dari kegagalan eksresi air dan natrium. Edema paru mikrovaskular merupakan bentuk edema paru renal primer lainnya, yang terjadi akibat adanya peningkatan permeabilitas kapiler paru, yang mungkin disebabkan karena penurunan tekanan onkotik plasma. Sedangkan edema paru sekunder sebagai konsekuensi ginjal dan jantung biasanya merupakan komplikasi dari kelainan jantung yang telah ada sebelumnya, misalnya akibat kardiomiopati hipertensif, anemik, maupun uremikum.5
Pada CKD, mekanisme utama yang mendasari terjadinya edema paru ialah fluid overload akibat retensi cairan dan natrium. Akibatnya terjadi peningkatan tekanan hidrostatik pada kapiler paru yang diikuti oleh terjadinya transudasi cairan dari kapiler paru ke dalam ruang interstisial maupun
alveolus paru. 5
Adanya cairan yang mengisi ruang alveolus mengakibatkan gangguan pada proses difusi gas, dari alveolus ke kapiler paru. Secara klinis, keadasan ini ditandai oleh adanya keluhan sesak nafas, rhonki pada pemeriksaan fisik, serta gambaran foto thorax yang mengarah pada kesan suatu edema paru.6 Pada kasus ini, pasien mengeluh sesak nafas dan batu berdahak disertai buih, ditemukan rhonki dan kesan edema pulmonum pada foto thoraxnya. Temuan-temuan ini mengarahkan dugaan adanya edema paru pada pasien ini.
Pembatasan asupan air pada pasien CKD sangat perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya edema dan komplikasi kardiovaskuler. Air yang masuk ke dalam tubuh dibuat seimbang dengan air yang keluar baik melalui urin maupun insesible
water loss (IWL) antara 500 sampai 800 ml/hari (sesuai dengan luas permukaan tubuh), maka air yang masuk dianjurkan 500 sampai 800 ml ditambah jumlah urin per hari.4
Pada pasien ini juga dilakukan pengaturan cairan masuk, guna mencegah volume overload yang akan memperberat edema paru dan edema tungkai yang telah terjadi sebelumnya. Produksi urin pasien perhari rata-rata 600 ml, ditambah IWL (500 ml), maka jumlah cairan keluar adalah 1100 ml, sehingga cairan yang diberikan juga harus sejumlah itu. Pasien diasumsikan dapat minum ± 2 gelas/hari (@ 250 ml), sehingga cairan yang diberikan melalui jalur parenteral ialah 600 ml/hari ~ 8 tetes/menit.
Faktor utama penyebab perburukan fungsi ginjal adalah terjadinya hiperfiltrasi glomerulus. Salah satu cara untuk mengurangi keadaan tersebut adalah dengan pembatasan asupan protein. Pembatasan asupan protein mulai dilakukan pada LFG ≤ 60 ml/menit/1,73m2. Jumlah protein yang dianjurkan ialah 0,6 – 0,8g/kgBB/hari, yang mana 0,35-0,50 gram diantaranya sebaiknya merupakan protein dengan nilai biologis tinggi. Jumlah kalori yang diberikan sebesar 30-35 kkal/kgBB/hari. Diet rendah garam (2-3 gr/hari) juga dianjurkan sebagai upaya untuk mencegah volume overload sekaligus sebagai terapi nonfarmakologis untuk mengatasi hipertensi.3,4 Pada pasien ini, diberikan diet tinggi kalori 35 kkal/kgBB/hari dan rendah protein (0,8 gr/kgBB/hari), serta diet rendah garam (250 mg/hari).
Untuk mengatasi hiperfosfatemia dapat diberikan pengikat fosfat. Agen yang banyak dipakai ialah garam kalsium, aluminium hidroksida, garam serta magnesium. Garam-garam ini diberikan secara oral, untuk menghambat absorpsi fosfat yang berasal dari makanan. Garam kaslium yang banyak dipakai adalah kalsium karbonat (CaCO3)
dan kalsium asetat. 4
Pada pasien ini diberikan CaCO3 dengan dosis 3 x 500 mg.

Pasien CKD mengalami peningkatan risiko athesklerosis karena tingginya prevalensi faktor risiko “tradisional” dan non
“tradisional”. 3
Peningkatan kadar homosistein merupakan salah satu faktor risiko non tradisional yang sering terjadi pada pasien CKD. Adapun mekanisme peningkatannya, hingga saat ini masih belum jelas. Homosistein berperan dalam memicu proses atherogenesis melalui beberapa cara: (1) menyebabkan kerusakan sel endotel pembuluh darah, (2) merangsang aktivasi trombosit, (3) mempengaruhi beberapa faktor yang terlibat dalam kaskade pembekuan darah, seperti menurunkan aktivitas anti thrombin, menghambat aktivitas kofaktor trombomodulin dan aktivasi protein C, meningkatkan aktivitas faktor V dan faktor XII, mengganggu sekresi faktor von Willebrand oleh endotel dan mengurangi sintesis prostasiklin.7
Pemberian asam folat merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya hiperhomosisteinemia pada pasien CKD, karena asam folat merupakan salah satu substansi penting yang diperlukan dalam metabolise homosistein Pada kasus ini, pasien diberikan terapi asam folat 2 x 2 mg.