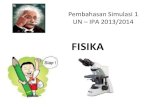Pembahasan
-
Upload
ririn-sutharini -
Category
Documents
-
view
254 -
download
26
description
Transcript of Pembahasan
PEMBAHASANPada praktikum kali ini dilakukan percobaan penetapan koefisien partisi suatu senyawa obat dalam campuran pelarut kloroform-air dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pH terhadap koefisien partisi obat yang bersifat asam lemah dalam campuran pelarut kloroform-air. Koefisien partisi didasarkan pada prinsip partisi yaitu suatu senyawa tertentu pada suhu dan tekanan tertentu akan terpartisi dengan sendirinya diantara dua pelarut yang tidak saling campur dengan perbandingan konsentrasi yang konstan atau tetap. Koefisien partisi adalah suatu pengukuran senyawa mendistribusikan dirinya sendiri ke dalam dua pelarut yang tidak saling campur dan sehingga dapat dibuat hubungan aktivitas obat dengan koefisien partisinya pada lemak atau air (Thomas, 2007). Peran penting dari mempelajari koefisien partisi dalam bidang farmasi berhubungan dengan kondisi dimanan membran tubuh manusia terdiri dari lipid bilayer sehingga untuk mengetahui absorpsi obat. Dimana dengan mengetahui koefisien partisi, rate limitting step dari obat dalam tubuh dapat diketahui sehingga seorang farmasis dapat menentukan onset obat dalam tubuh.Adapun manfaat koefisien partisi dalam dunia farmasi selain untuk mengetahui absorbsi obat tetapi dapat juga digunakan menentukan pra formulasi dan formulasi yang tepat dalam pembuatan sediaan farmasi. Koefisien partisi dapat juga dimanfaatkan dalam metode pemisahan, misalnya pada ekstraksi cair cair dan KLT. Dimana pada pemisahan tersebut kita dapat mengetahui sifat analit cenderung bersifat lipofil atau hidrofil sesuai dengan afinitas suatu analit terhadap dua pelarut yang tidak saling campur pada metode ekstraksi cair-cair atau afinitas suatu analit pada fase diam dan fase gerak pada metode KLT.Terdapat beberapa faktor yang memepengaruhi koefisien partisi suatu zat dalam sistem dua pelarut tertentu, salah satunya yaitu pengaruh pH. Pengaruh pH terhadap koefisien partisi adalah jika suatu senyawa, asam atau basa, mengalami ionisasi sebesar 50% (pH = pKa) maka koefisien partisinya setengah dari koefisien partisi obat-obat yang tidak mengalami ionisasi. Semakin besar pH makan semakin mudah terionisasi semakin kecil koefisien partisinya (Gandjar dan Rohman, 2007). Sebagian besar obat memiliki sifat asam lemah atau basa lemah sehingga apabila obat tersebut dilarutkan dalam air, maka sebagian akan terionisasi. Besar kecilnya fraksi obat yang terionkan sangat bergantung pada pH dari larutannya. Obat-obat yang berada dalam bentuk tidak terionkan akan lebih mudah larut dalam lipida, sedangkan obat-obat yang berada dalam bentuk terionkan kelarutannya akan kecil dalam lipida bahkan praktis tidak larut dalam lipida. Hal ini yang menunjukkan bahwa pH sangat berpengaruh dalam proses difusi suatu zat kecepatan absorbsi suatu obat yang bersifat asam lemah atau basa lemah ke dalam tubuh manusia.Bahan obat yang diidentifikasi distribusinya terhadap fase air dan fase organik adalah asam salisilat. Dimana asam salisilat memiliki sifat yaitu sukar larut dalam air dan dalam benzena, mudah larut dalam etanol dan dalam eter, larut dalam air mendidih dan agak sukar larut dalam kloroform (Depkes RI, 1995). Untuk melihat pengaruh pH terhadap koefisien partisi asam salisilat maka dibuat satu seri buffer asam salisilat yaitu pH 3, 4 dan 5. Pembuatan buffer asam salisilat dilakukan secara langsung yaitu dengan menambahkan Natrium Hidroksida (NaOH) pada asam salisilat sampai pH yang dikehendak tercapai, untuk memudahkan penetapan pH buffer digunakan larutan NaOH dengan konsentrasi yang 0,1 N. Pada setiap pembuatan buffer, pH larutan asam salisilat diukur dengan pH meter sehingga diketahui berapa pH yang telah dicapai tiap penambahan sejumlah NaOH. Dari pembuatan buffer selanjutnya diperoleh pH larutan asam salisilat dengan pH 3 ; pH 3,99 ; dan pH 4,99.Penetapan koefisien partisi dilakukan dengan menggunakan dua fase pelarut yang tidak saling campur, Sehingga masing-masing seri pH tersebut ditambahkan dengan kloroform. Sehingga nantinya dalam tabung tersebut akan terdapat tiga bahan yaitu air, kloroform, dan asam salisilat. Dalam percobaan penetapan koefisien partisi sebenarnya harus menggunakan corong pisah dengan tujuan untuk menghindari menguapnya kloroform dimana diketahui kloroform merupakan senyawa yang bersifat volatil, tetapi dalam percobaan ini digunakan Erlenmeyer sebagai medium tempat pemisahan. Hal ini akan menyebabkan terjadinya beberapa kesalahan yang dapat dikatagorikan sebagai kesalahan gamblang (gross error). Untuk meminimalisir penguapan dari kloroform maka pada saat dilakukan penggojogan, erlenmeyer ditutup dengan plastik ikan.Langkah pertama yang dilakukan dalam percobaan ini adalah dengan membuat larutan dapar asam salisilat pH 3, 4 dan 5. Larutan dapar asam salisilat dibuat dengan cara melarutkan 0,0345 gram asam salisilat dengan 100 mL aquades kemudian larutan asam salisilat ditambahkan dengan NaOH, sehingga akan menghasilkan larutan dapar asam salisilat akibat reaksi asam lemah (asam salisilat) dan basa kuat (NaOH) dan terbentuk Natrium salisilat volume 25 mL pada pH 3 , pH 3,99 , pH 4,99. Diketahuinya nilai pH diukur dengan menggunakan pH meter selama penambahan sejumlah NaOH. Berikut reaksi NaOH dengan asam salisilat :
Gambar 1. Reaksi asam salisilat dengan NaOHSebelum menggunakan alat pH meter untuk menentukan pH larutan dapar, pH meter harus dikalibrasi terlebih dahulu sehingga dihasilkan larutan dapar yang sesuai dengan pH yang diinginkan. Kalibrasi bertujuan untuk memastikan akuarasi alat yang digunakan dalam pH asam, netral dan basa agar dapat menghasilkan data yang valid. Kalibrasi dilakukan menggunakan larutan pH standar yang sudah tersedia di laboratorium. Pada proses kalibrasi ini digunakan larutan asam dengan pH 4 dan larutan netral dengan pH 7. Pada proses pembuatan larutan dapar salisilat penambahan NaOH yang berfungsi untuk menaikan pH larutan sampai mencapai pH yang diinginkan dan apabila pH yang didapat pada pH meter melebihi pH yang diinginkan, penurunan pH dapat dilakukan dengan penambahan tetes demi tetes HCl atau larutan asama lainnya. Pada akhirnya diperoleh larutan asama salisilat dengan pH 3 ; pH 3,99 ; dan pH 4,99. Pada praktikum ini digunakan larutan dapar salisilat pada berbagai pH bertujuan untuk mengetahui pengaruh pH terhadap koefisien partisi suatu obat, pada pH mana nilai koefisien partisi obat tersebut besar, sehingga obat mudah larut dalam lipid dan mudah untuk di absorbsi serta tujuan digunakan pH 3, 4 dan 5 pada pratikum ini adalah untuk menyamakan kondisi pada pH saluran percenaan terutama lambung. Pada pH 3 menunjukan lambung dalam keadaan kosong atau tidak terdapat makanan dan pH 5 menunjukan lambung dalam kondisi terisi makanan. Pada pH 3, 4 dan 5 asam salisilat yang bersifat asam lemah berada pada kondisi tidak terionkan sehingga lebih mudah larut dalam lemak sehingga lebih mudah diabsorbsi dalam lambung. Pada kondisi tidak terionkan, pada praktikum ini asam salisilat cenderung lebih larut dalam fase kloroform sehingga pada proses titrasi fase air lebih cepat dilakukan sebab kadar asam salisilat lebih sedikit dalam fase air sehingga NaOH yang diperlukan untuk habis bereaksi dengan asam salisilat lebih sedikit.
Tahap kedua, setelah larutan dapar asam salisilat berbagai pH yaitu pH 3; 3,99; 4,99 (sebanyak 2 seri), selanjutnya pada masing-masing pH ditambahkan 10 mL kloroform. Tujuan penambahan kloroform adalah untuk menciptakan dua fase yang tidak saling campur yaitu fase organik dan fase air. Kemudian setelah ditambahkan kloroform, larutan tersebut disonifikasi selama 15 menit, tujuan sonifikasi adalah untuk memperbesar kontak antara asam salisilat dengan fase air dan fase kloroform, sehingga terjadi transfer molekul antara air dan kloroform. Setelah disonifikasi selama 15 menit kemudian akan terjadi pemisahan antara dua fase tersebut dimana fase kloroform berada pada bagian bawah dan fase air berada pada bagian atas dikarenakan bobot jenis kloroform yaitu 1,480 gram/mL lebih besar dari bobot jenis air yaitu 1,00 gram/mL (Depkes RI, 1995). Pada pH 3 asam salisilat memiliki nilai pKa sebesar 3 sehingga pada pH 3 asam salisilat akan berada pada bentuk tidak terionkan dan lebih banyak yang terekstraksi kedalam fase organik yaitu fase kloroform dibandingkan pada pH 4 dan 5 (Martono, 2006). Semakin besar pH maka kelarutan asam salisilat akan berkurang pada fase organik.
Tahap ketiga, yaitu untuk mengetahui kadar asam salisilat dalam bentuk terionkan yang larut pada fase air digunakan metode titrasi asam basa dengan titran larutan NaOH 0,1 N. Penggunaan titrasi asam-basa untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi koefisien partisi karena jika solut merupakan asam lemah atau basa lemah (dan kebanyakan obat merupakan asam lemah atau basa lemah), maka adanya ionisasi adanya ionisasi dalam bentuk anion atau kation akan mengubah profil kelarutan obat secara nyata. Pada titrasi asam basa terjadi reaksi penetralan dari ion H+ asam salisilat dengan ion OH- dari NaOH untuk membentuk air yang bersifat netral. Jumlah NaOH yang diperlukan setara dengan jumlah asam salisilat yang bereaksi, sehingga jumlah asam salisilat dapat ditentukan secara stoikiometri. Dipipet sebanyak 5 ml larutan fase air pH 3; 3,99; 4,99 kemudian masing- masing dimasukan dalam erlenmeyer yang berbeda pada waktu ke nol, ditambahkan dengan 3 tetes indikator fenolftalein sampai terbentuk warna merah muda merah konstan. Perubahan warna pada fenolftalein dapat terjadi karena seiring meningkatnya pH akan terjadi proses penataan ulang pada struktur fenolftalein dimana terjadi perpindahan proton dari struktur fenol dari fenolftalein sehingga menyebabkan perubahan warna
Gambar 2. Penataan ulang struktur fenolftalein (Gandjar dan Rohman, 2007).Setelah titrasi pada waktu ke nol selesai dilakukan, masing-masing larutan kembali disonikasi selama 15 menit. Kemudian dilakukan titrasi kembali untuk memperoleh waktu titrasi pada waktu ke-15. Dari data yang diperoleh, konsentrasi rata-rata asam salisilat pada pH 3 adalah 2 x 10-2 M, pada pH 3,99 adalah 1,25 x 10-3 M dan pada pH 4,99 2 x 10-2 M. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan pustaka, dimana pada pustaka tertera semakin tinggi pH maka kelarutan obat yang bersifat asam lemah pada air semakin tinggi karena obat tersebut dalam bentuk terionkan. Senyawa organik dengan gugus fungsi yang bersifat asam atau basa dapat mengalami disosiasi atau ionisasi dalam larutan air sesuai dengan pengaruh pH larutan (Gandjar dan Rohman, 2007).Pada pratikum ini dilihat dari jenis pelarut dan zat uji yang digunakan memenuhi syarat koefisien partisi sejati yaitu pada pratikum ini digunakan pelarut yang tidak saling campur yaitu air dan kloroform, asam salisilat memiliki kelarutan yang rendah pada kedua pelarut yang tidak saling campur serta asam salisilat tidak mengalami asosiasi dan disosiasi. Maka pada percobaan ini digunakan koefisien partisi sejati.
Gambar 3. Kurva Perbandingan Konsentrasi terhadap waktu pada pH 3
Gambar 4. Kurva Perbandingan Konsentrasi terhadap waktu pada pH 3,99
Gambar 5. Kurva Perbandingan Konsentrasi terhadap waktu pada pH 4,99Tabel 1. Konsentrasi asam salisilat pada fase air dalam berbagai vairasi pH
pHKonsentrasi pada fase air
3,002 x 10-2 M
3,991,25 x 10-3 M
4,992 x 10-2 M
Gambar 6. Kurva Perbandingan konsentrasi asam salisilat terhadap variasi pHDari kurva perbandingan berbagai pH semakin besar pH, konsentrasi asam salisilat pada fase air semakin kecil yang menunjukkan bahwa koefisien partisinya semakin besar. Hal ini tidak sesuai dengan pustaka, yaitu menurut Sardjoko (1987) dimana pH berbanding terbalik dengan koefisien partisi. Pada obat yang bersifat asam, semakin besar pH suatu larutan, semakin kecil koefisien partisinya dan semakin rendah pH suatu larutan, semakin tinggi koefisien partisinya. Hal ini kemungkinan terjadi karena proses titrasi yang tidak sempurna seperti penambahan titran yang berlebih sehingga diperoleh warna merah keunguan pekat yang terbentuk mengindikasikan bahwa titik akhir titrasi telah terlampaui jauh. Disamping itu konsentrasi NaOH pada praktikum kali ini cukup besar yaitu 0,1 N. Penyimpangan ini juga dapat disebabkan karena tidak adanya standarisasi pada NaOH, standarisasi NaOH diperlukan karena NaOH bersifat tidak stabil di udara dan dalam udara terbuka dapat menyerap CO2 (Depkes RI, 1995). Sehingga pembakuan NaOH diperlukan untuk menjamin konsentrasi NaOH tidak berubah pada proses penyimpanan. Sehingga ketidakpastian kosentrasi NaOH dapat menggangu hasil dari penetapan kadar asam salisilat.Dari hasil perhitungan maka dapat ditetapkan nilai koefisien partisi asam salisilat dalam dua fase pelarut (Kloroform dan Air). Nilai koefisien yang digunakan merupakan nilai koefisien partisi semu (APC) karena dari sampel dan pelarut yang digunakan tidak dapat memenuhi persyaratan Koefisin partisi (TPC). Persyaratan yang tidak dapat dipenuhi adalah kadar obat yang digunakan lebih besar dari 0,01 M dan kelarutan solut dalam pelarut cukup besar tergantung pH. Dari Hasil perhitungan didapat nilai koefisien partisi (APC) dari masing-masing seri pelarut sebagai berikut pH 3 sebesar -0,47575; pH 3,99 sebesar -0,000043dan pH 4,99 sebesar -0,4995. Berikut kurva hubungan APC dengan fungsi pH.
Dari kurva diatas terlihat bahwa nilai APC tidak sesuai dengan yang diharapkan, dimana seharusnya semakin tinggi nilai pH nilai APC akan semakin rendah, begitu juga sebaliknya hal ini mungkin disebabkan penentuan titik akhir titrasi yang sulit dilakukan karena skala pada buret yang terbatas. Nilai koefisien partisi dapat dijelaskan secara sederhana, dimana diketahui bahwa jika suatu asam lemah dilarutkan dalam pelarut asam maka akan berada pada kondisi tak terionkan, dan semakin terionkan jika dilakukan peningkatan pH. Suatu senyawa pada kondisi tak terionkan relatif bersifat nonpolar dan senyawa yang terionkan relatif bersifat polar.
KESIMPULAN
1.1. Asam salisilat merupakan senyawa asam lemah sehingga dari kedaan tersebut dengan dilakukan peningkatan pH, asam salisilat akan semakin relatif bersifat lebih polar. Dengan teori umum kelarutan like dissolves like, semakin polar asam salisilat maka distribusinya akan semakin tinggi pada fase air (fase polar) sehingga nilai koefisien partisinya akan kecil, begitu juga sebaliknya semakin relatif non polar maka asam salisilat akan terdistribusi lebih banyak ke fase organik (fase nonpolar), sehingga nilai koefisien partisinya akan besar. 1.2. Metode yang digunakan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi koefisien partisi yaitu dengan menggunakan titrasi asam basa sehingga dapat diperoleh konsentrasi suatu larutan pada fase organik dan fase air atau kloroform-air dan dapat pula diketahui nilai APC atau koefisien partisi semu karena terdapat kemungkinan asam salisilat mengalami disosiasi karena pengaruh pH sehingga tidak memenuhi koefisien distribusi yang sebenarnya.
Asam salisilatNatrium salisilat
_1487577262.xlsChart1
0.0012
0.00066
0.0008
Kurva perbandingan Konsentrasi pada pH 4,02 terhadap waktu
Kurva perbandingan Konsentrasi pada pH 4,02 terhadap waktu
Sheet1
Kurva perbandingan Konsentrasi pada pH 4,02 terhadap waktu
00.0012
150.00066
300.0008
To resize chart data range, drag lower right corner of range.
_1487577266.xlsChart1
0.001
0.0012
0.0008
Kurva perbandingan Konsentrasi pada pH 2,99 terhadap waktu
Kurva perbandingan Konsentrasi pada pH 2,99 terhadap waktu
Sheet1
Kurva perbandingan Konsentrasi pada pH 2,99 terhadap waktu
00.001
150.0012
300.0008
To resize chart data range, drag lower right corner of range.
_1487577254.xlsChart1
0.00097
0.00088
0.0003
Kurva Perbandingan Konsentrasi asam Salisilat terhadap variasi pH
Kurva Perbandingan Konsentrasi asam Salisilat terhadap variasi pH
Sheet1
Kurva Perbandingan Konsentrasi asam Salisilat terhadap variasi pH
2.990.00097
4.020.00088
50.0003
To resize chart data range, drag lower right corner of range.
_1487577258.xlsChart1
0.00032
0.00032
0.00026
Kurva perbandingan Konsentrasi pada pH 5 terhadap waktu
Kurva perbandingan Konsentrasi pada pH 5 terhadap waktu
Sheet1
Kurva perbandingan Konsentrasi pada pH 5 terhadap waktu
00.00032
150.00032
300.00026
To resize chart data range, drag lower right corner of range.
_1487576159.xlsChart1
0.084
0.05
0.1
APC
APC vs Fungsi pH
Sheet1
PhAPC
30.084
40.05
50.1
Sheet1
APC
APC vs Fungsi pH
Sheet2
Sheet3