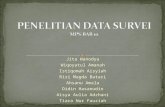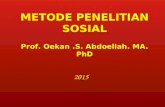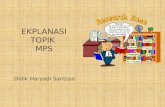MPS ERLIN
-
Upload
alfiahfajriani -
Category
Documents
-
view
72 -
download
6
Transcript of MPS ERLIN
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Karya sastra menerima pengaruh dari masyarakat dan sekaligus mampu memberi
pengaruh terhadap masyarakat (Semi, 1990: 73). Sastra dapat dikatakan sebagai cerminan
masyarakat, tetapi tidak berarti struktur masyarakat seluruhnya tergambarkan dalam sastra, yang
didapat di dalamnya adalah gambaran masalah masyarakat secara umum ditinjau dari sudut
lingkungan tertentu yang terbatas dan berperan sebagai mikrokosmos sosial, seperti lingkungan
bangsawan, penguasa, gelandangan, rakyat jelata, dan sebagainya. Sastra sebagai gambaran
masyarakat bukan berarti karya sastra tersebut menggambarkan keseluruhan warna dan rupa
masyarakat yang ada pada masa tertentu dengan permasalahan tertentu pula. Novel merupakan
salah satu di antara bentuk sastra yang paling peka terhadap cerminan masyarakat. Menurut
Johnson (Faruk, 2005: 45-46) novel mempresentasikan suatu gambaran yang jauh lebih realistik
mengenai kehidupan sosial. Ruang lingkup novel sangat memungkinkan untuk melukiskan
situasi lewat kejadian atau peristiwa yang dijalin oleh pengarang atau melalui tokoh-tokohnya.
Kenyataan dunia seakan-akan terekam dalam novel, berarti ia seperti kenyataan hidup yang
sebenarnya. Dunia novel adalah pengalaman pengarang yang sudah melewati perenungan kreasi
dan imajinasi sehingga dunia novel itu tidak harus terikat oleh dunia sebenarnya. Sketsa
kehidupan yang tergambar dalam novel akan memberi pengalaman baru bagi pembacanya,
karena apa yang ada dalam masyarakat tidak sama persis dengan apa yang ada dalam karya
sastra. Hal ini dapat diartikan pula bahwa pengalaman yang diperoleh pembaca akan membawa
dampak sosial bagi pembacanya melalui penafsiran-penafsirannya. Pembaca akan memperoleh
hal-hal yang mungkin tidak diperolehnya dalam kehidupan. Menurut Hauser (Ratna, 2003: 63),
karya seni sastra memberikan lebih banyak kemungkinan dipengaruhi oleh masyarakat, daripada
mempengaruhinya.
Sastra pada umumnya menampilkan gambaran kehidupan sosial tertentu. Kenyataan
sosial yang ditampilkan oleh pengarang dalam karyanya dapat merubah nili-nilai kehidupan
pembaca. Dalam fungsi ini Sarwadi (1974:2) menyatakan bahwa sastra dapat dijadikan sarana
kritik sosial.
Morte Parmi Les Vivants merupakan sebuah novel yang diangkat dari kisah nyata karya
Fredoune Sahebjam menampilkan gambaran kehidupan sosial mengenai penyiksaan dan
pelecehan terhadap wanita. Novel ini banyak membicarakan tentang ketimpangan sosial.
Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengambil judul “Ketidak Adilan
Gender” dalam Novel Morte Parmi Les Vivants Karya Freidoune Sahebjam:”. Hal ini
dikarenakan, bahwa novel tersebut menunjukkan adanya penggambaran kekerasan terhadap
perempuan. Usaha mengkaji Morte Parmi Les Vivants untuk mengungkap terjadinya kekerasan
terhadap perempuan.
1.2 Identifikasi Masalah
Setelah membaca Novel Morte Parmi Les Vivants Karya Freidoune Sahebjam, penulis
menemukan beberapa masalah sebagai berikut :
1. Latar Sosial Masyarakat di Afganistan
2. Latar Sosial Tokoh Utama
3. Isu Gender dalam Novel
4. Konflik yang melatar belakangi terjadinya ketidak adilan gender.
1.3 Batasan Masalah
Dalam penelitian ini penulis akan membatasi masalah yang akan dianalisis, penulis hanya
membahas mengenai :
1. Latar Sosial Tokoh Utama
2. Isu Gender dalam Novel
3. Konflik yang melatar belakangi terjadinya ketidak adilan gender.
1.4 Rumusan Masalah
Masalah yang akan digarap melalui penelitian ini terumuskan di bawah ini :
1. Bagaimana Latar kehidupan sosial Tokoh Utama pada novel “Jejak Luka Bilqis Karya
Freidoune Sahebjam” ?
2. Bagaimana isu gender digambarkan dalam novel “Jejak Luka Bilqis” Karya Maroune
Sahebjam.
3. Konflik apa saja kah yang melatar belakangi terjadinya ketidak adilan gender dalam
novel “Jejak Luka Bilqis” Karya Maroune Sahebjam.
1.5 Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui bagaimana Latar Sosial Tokoh Utama pada novel “Jejak Luka Bilqis”
Karya Maroune Sahebjam”
2. Untuk mengetahui gambaran isu gender yang terjadi dalam novel “Jejak Luka Bilqis”
Karya Maroune Sahebjam.
3. Untuk mengetahui konflik apa sajakah yang melatar belakangi ketidak adilan gender
dalam novel “Jejak Luka Bilqis” Karya Maroune Sahebjam.
1.6 Metodologi Penelitian
Dalam melakukan penelitian sebuah karya ilmiah, sangat diperlukan adanya sebuah
metode penelitian untuk membantu dalam proses penelitian. Dalam penyusunan penelitian ini,
penulis menggunakan metode yaitu, metode pengumpulan data yang dilakukan melalui
penelitian pustaka.
1.6.1 Metode Pengumpulan Data
Dalam penulisan ini, metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yaitu dengan
mengumpulkan data-data yang dapat mendukung didalam penulisan. Adapun data-data yang
dimaksud adalah data primer dan data sekunder yang terdiri atas:
1. Data Primer, adalah data yang menjadi sumber utama dalam penulisan ini yaitu Novel Jejak
Luka Bilqis Karya Maroune Sahebjam.
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber lainnya yang relevan dengan
obyek penelitian seperti pencarian melalui beberapa buku dan situs internet. Data ini penulis
gunakan sebagai pendukung asumsi maupun kesimpulan pada tahapan analisis.
1.6.2 Metode Analisis
Setelah semua data yang diperlukan untuk melakukan pengkajian, penulis melakukan
pengkajian data dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Akhirnya setelah melewati
seluruh tahapan analisis tersebut, penulis akan menarik kesimpulan berdasarkan hubungan
asosiatif yang terdapat dalam novel tersebut.
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Teori Penokohan
Ahli sastra sering menyebut prosa dengan istilah fiksi, istilah fiksi dipergunakan untuk
menyebut karya sastra yang isinya perpaduan antara kenyataan dan imajinasi. Fiksi yang baik
menggambarkan kehidupan yang mengundang simpati pembaca, tanggapan pembaca, dan
mendidik moral pembaca. Seperti sebuah novel yang merupakan suatu totalitas mempunyai
bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan dengan yang lain secara erat dan saling
bergantung. Unsur-unsur inilah yang kemudian menjadi pembangun sebuah novel, yaitu unsur
intrinsik dan unsur ekstrinsik.Unsur intrinsik ialah unsur-unsur yang membangun karya sastra itu
sendiri. Unsur-unsur inilah yang menyebabkan karya sastra hadir sebagai karya sastra, unsur-
unsur yang secara faktual akan dijumpai jika orang membaca karya sastra. Unsur ekstrinsik
adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra namun mempengaruhi kehadiran karya sastra
sebagai karya seni. Unsur ekstrinsik karya fiksi sebagai aspek yang berada di luar sastra seolah-
olah berpisah atau berdiri sendiri dan tidak memiliki kaitan dengan unsur intrinsik.Namun
sebenarnya antara unsur intrinsik dan ekstrinsik itu saling berhubungan tidak terlepas antara yang
satu dengan yang lain. Unsur ekstrinsik antara lain aspek historis yaitu kaitannya antara sastra
dan latar belakang sejarah, aspek sosiologis berkaitan antara sastra dengan masyarakat dalam
berinteraksi satu dengan yang lain, aspek psikologis yang berkaitan antara sastra dengan
kejiwaan manusia, aspek budaya yang berkaitan antara sastra dengan adat istiadat atau kebiasaan
yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, aspek agama/religius kaitannya dengan sastra sangat
erat karena keyakinan adanya nilai religius dalam karya sasrta sudah ada sejak lama, keyakinan
adanya nilai religius dalam karya sastra merupakan akibat logis dari kenyataan bahwa sastra dari
pengarang yang homoreligius (dalam skripsi Chairiah, 2010:19-20).
Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa unsur pembangun novel
ada dua,yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kedua unsur tersebut memiliki keterkaitan
antara yang satu dengan yang lain untuk menciptakan suatu karya sastra yang bernilai seni.
Struktur yang hendak dikaji dalam novel ini hanya akan dititikberatkan pada tokoh dan
penokohan.Tokoh dalam suatu cerita rekaan merupakan unsur penting yang menghidupkan
cerita. Kehadiran tokoh dalam cerita berkaitan dengan terciptanya konflik, dalam hal ini tokoh
berperan membuat konflik dalam sebuah cerita rekaan (Wiyatmi, 2006: 30).Pembicaraan
mengenai penokohan dalam cerita rekaan memiliki keterkaitan dengan tokoh. Istilah‘tokoh’
menunjuk pada pelaku dalam cerita sedangkan ‘penokohan’ menunjukkan pada sifat, watak atau
karakter yang melingkupi diri tokoh yang ada. Penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas
tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita (Wiyatmi, 2006: 31).
Penokohan dapat juga dikatakan sebagai proses penampilan tokoh sebagai pembawa
peran watak tokoh dalam suatu cerita. “Penokohan harus mampu menciptakan citra tokoh. Oleh
karena itu, tokohtokoh harus dihidupkan” (Wardani, 2009: 40). Berdasarkan uraian di atas, dapat
disimpulkan bahwa penokohan adalah cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan
watak tokoh-tokoh dalam sebuah cerita rekaan. Penciptaan citra atau karakter ini merupakan
hasil imajinasi pengarang untuk dimunculkan dalam cerita sesuai dengan keadaan yang
diinginkan .
Penokohan dalam cerita dapat disajikan melalui dua metode, yaitu metode langsung
(analitik) dan metode tidak langsung (dramatik). Metode langsung (analitik) adalah teknik
pelukisan tokoh cerita yang memberikan deskripsi, uraian atau penjelasan langsung. Pengarang
memberikan komentar tentang tokoh cerita berupa lukisan sikap, sifat, watak, tingkah laku, dan
ciri fisiknya. Metode tidak langsung (dramatik) adalah teknik pengarang mendeskripsikan tokoh
dengan membiarkan tokoh-tokoh tersebut saling menunjukkan kepribadiannya masing-masing,
melalui berbagai aktivitas yang dilakukan baik secara verbal maupun nonverbal, seperti tingkah
laku, sikap dan peristiwa yang terjadi (Wiyatmi, 2006:32). Setiap tokoh mempunyai wataknya
sendiri-sendiri.
Tokoh adalah bahan yang paling aktif menjadi penggerak jalan cerita karena tokoh ini
berpribadi, berwatak, dan memiliki sifat-sifat karakteristik tiga dimensional, yaitu :
1. Dimensi fisiologis ialah ciri-ciri badan, misalnya usia (tingkat kedewasaan), jenis kelamin,
keadaan tubuhnya, ciri-ciri muka dan ciri-ciri badani yang lain.
2. Dimensi sosiologis ialah ciri-ciri kehidupan masyarakat, misalnya status sosial, pekerjaan,
jabatan atau peran dalam masyarakat, tingkat pendidikan, pandangan hidup, agama, sosial,
suku bangsa dan keturunan.
3. Dimensi psikologis ialah latar belakang kejiwaan, misalnya mentalitas, ukuran moral,
temperamen, keinginan, perasaan pribadi, IQ dan tingkat kecerdasan keahlian khusus
(Wardani, 2009: 41).
2.2 Teori Gender
Kata Gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin (John M. echols dan
Hassan Sadhily, 1983: 256). Secara umum, pengertian Gender adalah perbedaan yang tampak
antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Dalam Women Studies
Ensiklopedia dijelaskan bahwa Gender adalah suatu konsep kultural, berupaya membuat
perbedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara
laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam buku Sex and Gender yang
ditulis oleh Hilary M. Lips mengartikan Gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-
laki dan perempuan. Misalnya; perempuan dikenal dengan lemah lembut, cantik, emosional dan
keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri-ciri dari sifat itu
merupakan sifat yang dapat dipertukarkan, misalnya ada laki-laki yang lemah lembut, ada
perempuan yang kuat, rasional dan perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat tersebut dapat terjadi
dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain (Mansour Fakih 1999: 8-9)
Heddy Shri Ahimsha Putra (2000) menegasakan bahwa istilah Gender dapat dibedakan ke
dalam beberapa pengertian berikut ini: Gender sebagai suatu istilah asing dengan makna tertentu,
Gender sebagai suatu fenomena sosial budaya, Gender sebagai suatu kesadaran sosial, Gender
sebagai suatu persoalan sosial budaya, Gender sebagai sebuah konsep untuk analisis, Gender
sebagai sebuah perspektif untuk memandang kenyataan. Epistimologi penelitian Gender secara
garis besar bertitik tolak pada paradigma feminisme yang mengikuti dua teori yaitu;
fungsionalisme struktural dan konflik. Aliran fungsionalisme struktural tersebut berangkat dari
asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas berbagai bagian yang saling mempengaruhi. Teori
tersebut mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di dalam masyarakat. Teori
fungsionalis dan sosiologi secara inhern bersifat konservatif dapat dihubungkan dengan karya-
karya August Comte (1798-1857), Herbart Spincer (1820-1930), dan masih banyak para
ilmuwan yang lain.
Teori fungsionalis kontemporer memusatkan pada isu-isu mengenai stabilitas sosial dan
harmonis. Perubahan sosial dilukiskan sebagai evolusi alamiah yang merupakan respon terhadap
ketidakseimbangan antar fungsi sosial dengan struktur peran-peran sosial. Perubahan sosial
secara cepat dianggap perubahan disfungsional. Hilary M. Lips dan S. A. Shield membedakan
teori strukturalis dan teori fungsionalis. Teori strukturalis condong ke sosiologi, sedangkan teori
fungsionalis lebih condong ke psikologis namun keduanya mempunyai kesimpulan yang sama.
Dalam teori itu, hubungan antara laki-laki dan perempuan lebih merupakan kelestarian,
keharmonisan daripada bentuk persaingan (Talcott Parson dan Robert Bales). System nilai
senantiasa bekerja dan berfungsi untuk menciptakan keseimbangan dalam masyarakat, misalnya
laki-laki sebagi pemburu dan perempuan sebagai peramu. Perempuan dengan fungsi
reproduksinya menuntut untuk berada pada peran domestik. Sedangkan laki-laki pemegang
peran publik. Dalam masyarakat seperti itu, stratifikasi peran gender ditentukan oleh jenis
kelamin (sex). Kritik terhadap aliran tersebut bahwa struktur keluarga kecil yang menjadi ciri
khas keluarga modern menyebabkan perubahan dalam masyarakat. Jika dulu tugas dan tanggung
jawab keluarga dipikul bersama-sama, dewasa ini fungsi tersebut tidak selalu dapat dilakukan.
Sedangkan teori konflik diidentikkan dengan teori marxis karena bersumber pada tulisan dan
pikiran Karl Marx. Menurut teori itu, perubahan sosial terjadi melalui preses dialektika, teori itu
berasumsi bahwa dalam susunan masyarakat terdapat beberapa kelas yang saling
memperebutkan pengaruh dan kekuasaan.
Friedrich Engels, melengkapi pendapat Marx bahwa perbedaan dan ketimpangan Gender tidak
disebabkan oleh perbedaan jenis kelamin (biologis), akan tetapi merupakan divine creation.
Engels memandang masyarakat primitiv lebih bersikap egaliter karena ketika itu belum dikenal
adanya surplus penghasilan. Mereka hidup secara nomaden sehingga belum dikenal adanya
pemilikan secara pribadi. Rumah tangga dibangun atas peran komunitas. Perempuan memiliki
peran dan kontribusi yang sama dengan laki-laki. Menurut Marxisme, penindasan perempuan
dalam dunia kapitalis karena mendatangkan keuntungan. Pertama, eksploitasi wanita dalam
rumah tangga akan meningkatkan produksi kerja laki-laki di pabrik-pabrik. Kedua, perempuan
yang terlibat peran produksi menjadi buruh murah, memungkinkan dapat menekan biaya
produksi, sehingga perusahaan lebih diuntungkan. Ketiga, masuknya perempuan sebagai buruh
murah dan mengkondisikan buruh-buruh cadangan akan memperkuat posisi tawar pihak
kapitalis, mengancam solidaritas kaum buruh. Ketiga, hal tersebut dapat mempercepat akumulasi
kapital bagi kapitalis (Mansour Fakih, 1996: 87-88). Sedangkan Dahrendarf dan Randall Collins
tidak sepenuhnya sependapat dengan Marx dan Engels. Menurutnya konflik tidak hanya terjadi
pada perjuangan pekerja kepada pemilik modal, tetapi juga disebabkan oleh faktor kesenjangan
antara anak dan orang tua, istri dengan suami, yunior dengan senior dan sebagainya. Dari teori-
teori diatas, berkembang dan melahirkan aliran-aliran Feminisme berikut ini: Feminisme Liberal,
Feminisme Marxis, Feminisme Radikal, Feminisme Sosialis, Feminisme Teologis.
Pandangan para ahli psikologi mengenai gender adalah menyangkut karakteristik kepribadian
yang dimiliki oleh individu, yaitu maskulin, feminine, androgini dan tak terbedakan. Masing
masing karakteristik kepribadian gender tersebut memiliki karakteristik tersendiri, yang
mempengaruhi perilaku seseorang.
1. Konsep umum gender
The Oxford Encyclopedia Of The Modern World (Esposito, 1995 gender adalah
pengelompokkan individu dalam tata bahasa yang digunakan untuk menunjukkan ada tidaknya
kepemilikan terhadap satu ciri jenis kelamin tertentu. Gender menurut Illich (1998) merupakan
satu diantara tiga jenis kata sandang dalam tata bahasa, yang kurang lebih berkaitan dengan
pembedaan jenis kelamin, yang membeda-bedakan kata benda menurut sifat penyesuaian dan
diperlukan ketika kata benda itu dipakai dalam sebuah kalimat. Kata-kata benda dalam bahasa
Inggris biasanya digolong-golongkan menurut gender maskulin, feminin dan netral. Secara
terminologis, gender digunakan untuk menandai segala sesuatu yang ada di dalam masyarakat
“vernacular” (bahasa, tingkah laku, pikiran, makanan, ruang, waktu, harta milik, tabu, alat-alat
produksi dan sebagainya). Secara konseptual gender berguna untuk mengadakan kajian terhadap
pola hubungan sosial laki-laki dan perempuan dalam berbagai masyarakat yang berbeda (Fakih,
1997). Istilah gender berbeda dengan istilah sex atau jenis kelamin menunjuk pada perbedaan
laki-laki dan perempuan secara biologis (kodrat), gender lebih mendekati arti jenis kelamin dari
sudut pandang sosial (interpensi sosial kultural), seperangkat peran seperti apa yang seharusnya
dan apa yang seharusnya dilakukan laki-laki dan perempuan (Mansur Fakih, 1996). Lips (1988),
Abbott (1992), Mosse (1996), membedakan kata sex sebagai(ciri- ciri biologis, fisik tertentu
jenis kelamin biologis) Sex merupakan pembagian 2 jenis kelamin manusia yang ditentukan
secara biologis (kodrat), individu dilahirkan sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan.
dan gender lebih mendekati arti jenis kelamin dari sudut pandang sosial. Gender merupakan jenis
interpretasi sosio-kultural, seperangkat peran yang dikontruksi oleh masyarakat bagaimana
menjadi laki-laki (kuat, tegas, perkasa, kasar, dst) atau perempuan (taat, penurut, lemah, keibuan,
penuh kasih sayang). Perangkat perilaku khusus ini mencakup penampilan, pakaian, sikap,
kepribadian, seksualitas, tanggung jawab keluarga dan sebagainya.
2. Konsep Psikologi mengenai Gender
Gender (para psikolog) di definisikan sebagai suatu gambaran sifat, sikap dan perilaku laki-laki
dan perempuan (Sahrah, 1996). Suatu kepribadian dan perilaku yang dibedakan atas tipe
maskulin dan feminin (Whitley dan Bernard dalam Kuwato, 1992), seperangkat peran gender
tentang seperti apa seharusnya dan bagaimana seharusnya dilakukan, dirasakan dan dipikirkan
oleh individu sebagai maskulin dan feminin (Santrock, 1998., Berry, dkk., 1999). Menurut
Sandra Bem (1981a), tokoh sentral psikologi gender, gender merupakan karakteristik
kepribadian, seseorang yang dipengaruhi oleh peran gender yang dimilikinya. Bem (1981a)
mengelompokkannya menjadi 4 klasifikasi yaitu maskulin, feminin, androgini dan
takterbedakan. Masing-masing klasifikasi tersebut memiliki karakteristik tersendiri, yang
mempengaruhi perilaku seorang individu, individu dengan peran gender feminin misalnya
berbeda perilaku prososialnya dengan realitas kehidupan sosial bila dibandingkan dengan peran
gender maskulin, hal ini disebabkan karena individu dengan peran gender feminin memiliki
karakteristik seperti: hangat dalan hubungan interpersonal, suka berafiliasi, kompromistik,
sensitif terhadap keberadaan orang (Pendhazur dan Teenbaum, 1979), suka merasa kasihan,
senang pada kehidupan kelompok (Sahrah, 1996), sebaliknya maskulin, yaitu kurang hangat dan
kurang dapat mengekspresikan kehangatan, kurang responsif terhadap hal-hal yang berhubungan
dengan emosi (Bakan dalam Sahrah, 1996). Individu yang memiliki peran gender androgini
memiliki tingkat kemandirian lebih tinggi dibandingkan dengan peran gender lainnya (Nuryoto,
1992). Setiap kebudayaan menurut Santrock (1998), dan Berry (1999) mendefinisikan peran
gender dari berbagai tugas, aktivitas, sifat kepribadian yang dianggapnya pantas bagi seorang
individu (laki-laki dan perempuan). Sebelum pertengahan tahun 70-an gender diartikan sebagai
suatu gambaran dari tingkah laku dan sikap-sikap yang secara umum telah disetujui seseorang
sebagai suatu yang maskulin atau feminine saja. Laki-laki diharapkan selalu mempunyai sifat
maskulin sedang perempuan mempunyai sifat feminin. Sedangkan Bem Sex Role Inventory
(BSRI) mengenalkan peran gender androgini.
3. Teori pembentukan peran gender
a. Teori biologis
Perbedaan peran gender ada hubungannya dengan aspek biologis, bahkan tidak lepas dari
pengaruh perbedaan biologis (sex) laki-laki dan perempuan. Perbedaan biologis laki-laki dan
perempuan adalah alami (nature), begitu pula sifat peran gender (maskulin dan feminin) yang
dibentuknya. Perbedaan biologis menyebabkan terjadinya perbedaan peran antara laki-laki dan
perempuan. Oleh karena itu, sifat stereotype peran gender antaara lakki-laki dan perempuan sulit
untuk dirubah. Perbedaan fisik antara laki-lakidan perempuan memberikan implikasi yang
signifikan pada kehidupan publik perempuan, sehingga perempuan lebih sedikit perannya
dibanding laki-laki (Megawangi, 2001)
b. Teori cultural
Pembentukan peran gender bukan disebabkan oleh adanya perbedaan biologis antara laki-
laki dan perempuan, melainkan karena adanya sosialisasi atau kulturalisasi. Teori ini tidak
mengakui adanya sifat alami peran gender (nature), tetapi yang ada adalah sifat peran gender
yang dikonstruksi oleh sosial budaya melalui proses sosialisasi. Teori ini membedakan antara
jenis kelamin (sex) konsep nature, dan gender konsep nurture. Sesuatu yang nature tidak dapat
berubah, sedangkan peran gender dapat diubah baik melalui budaya maupun dengan teknologi.
Pandangan teori ini dianut oleh sebagian besar feminis yang menginginkan transformasi sosial,
sehingga perbedaan atau dikotomi peran gender laki-laki dan perempuan dapat ditiadakan
(Megawangi, 2001)
c. Teori Freudian
Menurut teori ini, anak belajar tentang peran gender dari lingkungan sekitarnya, karena anak
mengidentifikasikan perlakuan orang tuanya. Anak laki-laki mengidentifikasi perlakuan ayahnya
sehingga bagaimana perilaku seorang laki-laki. Demikian halnya anak perempuan yang belajar
dari ibunya. Proses pengidentifikasian ini ditemukan anak dari perbedaan genital jenis kelamin.
d. Teori belajar sosial
Teori belajar sosial meletakkan sumber sex typing pada latihan membedakan jenis kelamin
dalam komunitas masyarakat, keutamaan dari teori ini adalah mengimplikasikan perkembangan
psikologi laki-laki dan perempuan mempunyai prinsip umum sama dengan proses belajar pada
umumnya. Jadi, jenis kelamin (seks) tidak dipertimbangkan istimewa; tidak ada mekanisme atau
proses psikologis khusus yang harus dipostulasikan dalam menjelaskan bagaimana anak-anak
menjadi sex typed. Karena telah termasuk penjelasan bagaimana anak-anak belajar perilaku
sosial yang lain. Teori ini memperlakukan anak sebagai agen aktif yang berusaha
mengorganisasikan & memahami dunia sosialnya.
e. Teori perkembangan koognitif
Individu sebagai organisme aktif, dinamis serta memiliki kemauan berpikir. Individu mampu
dan berhak membuat pertimbangan dan keputusan sesuai dengan kemauan dan kemampuannya
sendiri. Sex typing mengikuti prinsip natural dan tidak dapat dihindari dari perkembangan
kognisi. Individu bekerja aktif memahami dunia sosial mereka, dan akan melakukan kategorisasi
terhadap dirinya sendiri (self-categorization) sebagai laki-laki dan perempuan. Dasar kategorisasi
diri ini yang menentukan penilaian dasar. Seorang laki-laki misalnya akan stabil
mengidentifikasikan dirinya sendiri sebagai laki-laki, kemudian ia akan menilai objek-objek
yang berkenaan dengan jenis kelaminnya secara positif dan bertindak secara konsisten dengan
identitas jenis kelaminnya.
f. Teori skema gender
Teori ini (Bem, 1974), merupakan kombinasi dari teori belajar sosial dan teori
perkembangan kognitif. Pengaruh lingkungan sosial dan peran individu keduanya dipadukan
dalam pembentukan peran gender melalui skema gender. Teori skema gender berasumsi bahwa
sex typing adalah fenomena yang dipelajari, oleh karena itu dapat dihindari atau dimodifikasi.
Dengan demikian skema gender merupakan sejumlah persepsi (kognisi) dan proses belajar
individu terhadap atribut-atribut dan perilaku yang sesuai jenis kelaminnya atau menurut label
yang diberikan komunitas sosial atau kebudayaan kepadanya (Bem, 1981b). Dengan teori ini
dapat pula diketahui bahwa jenis kelamin tidak selalu berhubungan dengan peran gendernya.
Kebudayaanlah yang membuat gender yang menjadi kognisi penting di antara berbagai kategori
sosial yang ada (ras, etnik, dan religiusitas). Mayoritas kebudayaan mengajarkan perkembangan
individu yaitu: pertama, mengajarkan jaringan subtansi dari asosiasi-asosiasi yang dapat dilayani
sebagai skema kognisi; kedua, mengajarkan dikotomi tertentu tentang laki-laki dan perempuan
secara intensif dan ekstensif dalam setiap daerah pengalaman manusia. Manusia menunjukkan
pentingnya fungsi perbedaan gender sebagai dasar perbedaan adanya norma, tabu dan susunan
kelembagaan (Bem,1981a).
BAB III
ANALISIS DATA
3.1 Sinopsis Novel
Novel ini bercerita tentang seorang anak gadis yang bernama Bilqis, seorang anak yang
ditinggal mati oleh ayahnya dan tinggal bersama ibunya dan beberapa orang adik-adiknya, pada
masa ini di sebuah tempat terpelosok dimana si Bilqis menghabiskan waktunya bersama
keluarga dan juga bersama warga setempat, diwilayah ini telah terjadi wajib militer dan
mengharuskan ayah Bilqis harus patuh pada peratutan pemerintah. Sejak saat itu Ayah Bilqis
tidak terdengar lagi kabarnya, setahun kemudian di kampung itu kedatangan sekompi tentara
perdamain Soviet dan para tentara itu membangun kompi di kawasan kampung Bilqis, beberapa
bulan kemudian terjadilah sebuah peristiwa yang dimana dikampung itu menjadi sebuah aib
dan kehinaan yang luar biasa, si Bilqis diperkosa oleh beberapa orang tentara Soviet yang
hendak lewat disebuah sungai dimana si Bilqis sementara mencuci pakaian, kabar ini pun
terdengar oleh Ibu Bilqis, dan sejak saat itu dianggap hina oleh ibunya dikarenakan si Bilqis
adalah pembawa aib keluarga dan diperlakukan layaknya binatang oleh ibunya bahkan adik-
adiknyapun memperlakukan hal yang sama terhadap kakaknya si Bilqis. Dengan bantuan
tetangga Ibu Bilqis akhirnya menjual Bilqis kepada seorang pedagang disebuah kota yang tidak
terlalu jauh jaraknya dari desa Bilqis. Disitu si Bilqis bekerja sebagai penjaga toko dan tetap
saja Bilqis mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari seorang majikannya, dan dia pun
bertemu dengan seorang pemuda setempat dan berhasil membawa Bilqis untuk tinggal bersama
keluarga pemuda tersebut, setelah beberapa bulan pemuda itu mengetahui bahwa Bilqis adalah
korban pemerkosaan dan pemuda itu akhirnya memukul Bilqis tanpa alasan yang tepat dan si
Bilqis pun lari kesuatu tempat dimana di tempat itu dia tinggal bersama janda-janda korban
perang dan si Bilqis diperlakukan sangat baik oleh warga setempat dan bahkan dia dijodohkan
dengan anak wali kota setempat, tetapi karena si Bilqis takut ketahuan bahwa dia adalah
seorang korban pemerkosaan, Bilqispun melarikan diri kesebuah kota besar, Bilqispun
ditemukan oleh seorang polisi dari kota tersebut dan dipekerjakan sebagai pembantu rumah
tangga dirumah saudara polisi tersebut, tetapi sang polisi mengetahui latar belakang Bilqis,
polisi itu akhirnya memperlakukan Bilqis sebagai pelampiasan nafsu polisi tersebut. Kemudian
polisi itu mempekerjakan Bilqis kesebuah tempat prostitusi, ditempat itu Bilqis bekerja sebagai
pemuas hasrat lelaki hidung belang. Begitulah kehidupan dari seorang Bilqis yang merasa
selalu mendapatkan ketidak adilan dan mendapatkan perlakuan baik secara fisik maupun
seksual, hingga akhirnya dia menjadi seorang perempuan yang baik karena selalu menafkahi
fakir miskin disekitarnya.
3.2 Adanya Ketidak Adilan Gender Dalam Cerita
Adapun bentuk-bentuk ketidak adilan gender dalam cerita :
1. Vassili menyambarnya dan mendekap kedadanya. Tak ada teriakan keluar dari mulut Bilqis.
Ia hanya pasrah dan memejamkan mata. “Tuhan Maafkan aku..” Vassili merebahkan diri
disamping Bilqis dan mencoba menarik roknya. Ia tak berhasil dan mulai marah, Belati
keluar dari kantong dan merobek rok berbunga milik Bilqis.
Analisis :
2. Bilqis diam dan membiarkannya terjadi. Seperti binatang kelaparan, laki-laki itu
melampiaskan nafsu dan mengembuskan napas puas. Sejak bebrapa bulan, ia merindukan
prempuan dan rumah bordil herat membuatnya muak. Ia mengerahkan semua kekuatannya,
semua keinginannya, penuh rasa frustasi sejak dikenakannya seragam militer.
“Serguei, apa yang kaulakukan ?” tiga tentara memerhatikannya dengan penuh
keingintahuan. Serguei berdiri dan memanggil teman-temannya. “sini, ada barang bagus!
Gadis ini pasrah, ia masih bocah!”
Tiga temannya menuruni tebing dengan cepat dan melihat Bilqis. Lalu, bergiliran, seperti
binatang, mereka menggagahi tubuh yang seakan-akan mati, dan memuaskan keinginan dan
fantasi mereka.
3. Kedua pembantu mewajibkannya untuk membantu mencuci dan memeras kain, membawa
keranjang atau mengganti air kolam. Ketika ia bekerja agak lambat, kepalanya dipukul atau
tak diberi makan. Ketika pekerjaannya tak sempurna, ia harus mengulanginya, sekalipun
malam telah larut, sampai majikannya puas.
4. Hamid menghujaninya dengan pukulan, menacakari wajahnya, menarik jilbabnya,
menyobek bajunya, dan membekapnya dengan bantal kursi hingga sesak napas.
5. Polisi itu memegang pinggang dan menarik Bilqis kepelukannya. Laki-laki itu membuka
jilbab Bilqis dan menahannya agar tak lari. Dan berbisik ditelinga Bilqis “Kau faeche, aku
tahu, kau sundal !! ia melepas kancing lagi dan berkata, “Aku datang kapanpun aku mau.
Perbuatan itu berlangsung berbulan-bulan. Polisis itu datang sekali atau dua kali.
6. Ia memukul Bilqis dengan keras dan menariknya. Tanpa menunggu perintah, Bilqis
membuka cadarnya, melepas sepatu, dan merebahkan diri. Setelah tenang, ia menodai Bilqis
seperti binatang buas.
BAB IV
KESIMPULAN
Setelah melihat dan menganalisa secara seksama data diatas, penulis merasa bahwa novel “Jejak
Luka Bilqis” karya Freidoune sahebjam sangat bernuansa ketidak adilan pada gender. Ini
dikarenakan dari berbagai latar kehidupan seorang perempuan yang selalu mendapatkan
perlakuan yang tidak manusiawi. Terkadang kehidupan sosial dari suatu wilayah berdampak
pada adanya kehidupan yang monoton dan tidak teratur. Keadilan seakan menjadi sebuah
tanggung jawab pribadi. Ketika kita membaca novel ini, kita akan terbawa suasana dimana rasa
ketidak manusiawian itu muncul terhadap perempuan sebagai mahluk yang lemah dan tak
berdaya.
. DAFTAR PUSTAKA
Fakih, Mansour, 1996, Analisa Gender & Transformasi Sosial.
Moore, Henrietta L. 1988 Feminism and Antropology, Cambridge, Polity Press.
Abdullah, I . (Ed). 1997. Sangkan Peran Gender. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Pusat
penelitian kependudukan.
Baidhawy, Zakyuddin. (Ed). 1997. Wacana Teologi Feminis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18102/3/Chapter%20II.pdf dikutip jam 15. 19 tanggal
15 Mei 2013
http://www.sarjanaku.com/2012/06/pengertian-gender-menurut-para-ahli.html dikutip jam 16. 05
tanggal 15 Mei 2013