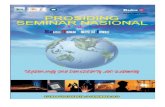makalah dpt.docx
-
Upload
ahmad-said -
Category
Documents
-
view
79 -
download
4
Transcript of makalah dpt.docx

A. NAMA PENYAKIT: Tungro tanaman padi
B. INANG: Padi ( Oryza sativa )
C. ARTI PENTING PENYAKIT
Tungro disebabkan oleh infeksi dua macam virus, yaitu rice tungro bacilliform
badnavirus (RTBV) and rice tungro spherical waikavirus (RTSV). RTBV menyebabkan
gejala tungro meliputi perubahan warna daun kuning sampai oranye dan tanaman menjadi
kerdil. RTSV sendiri tidak menyebabkan gejala yang jelas, hanya kerdil ringan, tetapi
memperparah gejala yang disebabkan oleh RTBV. Biasanya terjadi pada fase
pertumbuhan vegetatif dan menyebabkan berkurangnya jumlah anakan.
D. Patogen
1. Morfologi
Bentuk partikel RTBV adalah bacilliform dengan diameter 30-35 nm dan panjang
kira-kira 100-300 nm yang bervariasi antara isolat (Hibino et al., 1978). Asam nukleat
RTBV adalah DNA utas ganda dan bulat lebih kurang 8 kb (kilo base). Asam nukleat
tersebut mengandung dua daerah yang tidak bersambung yang merupakan hasil dari
proses replikasi oleh reverse transcriptase dan mempunyai empat open reading frames
(ORFs) (Hull, 1996).
RTSV mempunyai genom poliadenil ssRNA, unipartit, terbungkus partikel
isometrik dengan diameter 30 nm (Hibino et al., 1978). Genom RNA RTSV kira-kira
11 kb dan protein selubungnya terdiri dari dua jenis molekul protein (Agrios, 1997).
2. Klasifikasi
a. (RTBV)
Group : Group VII (dsDNA-RT)
Family : Caulimoviridae
Genus : Tungrovirus
Species : Rice tungro bacilliform virus
b. (RTSV)
Group : Group IV {(+)ssRNA}
Family : Sequiviridae
Genus : Waikavirus
Spesies : Rice tungro spherical virus
1

3. Sifat patogen
Tungro merupakan salah satu penyakit penting pada tanaman padi yang menjadi
permasalahan dalam usaha peningkatan produksi padi nasional. Penyakit yang
disebabkan oleh dua jenis virus (virus bulat dan virus batang) yang ditularkan oleh
wereng hijau Nephotettix virescens telah menyebar dan menyebabkan kehilangan hasil
di beberapa sentra produksi padi di Indonesia. Tiga faktor utama penyebab terjadinya
serangan tungro adalah ketersediaan sumber inokulum virus, adanya serangga penular
dan keberadaan tanaman peka.
E. Gejala penyakit
Gejala utama pada tanaman padi yang terinfeksi virus
tungro adalah perubahan warna daun menjadi kuning-oranye,
kerdil, dan penurunan jumlah anakan (Hibino et al., 1978). Virus
tungro juga menyebabkan helaian dan pelepah daun memendek,
dan jumlah anakan sedikit. Pada bagian bawah helai duan muda
terjapit oleh pelepah daun sehingga daunnya terpuntir dan
menggulung. Daun tanaman padi yang terinfeksi virus tungro kadang terlihat ramping
menggulung keluar dan seperti spiral. Selanjutnya infeksi virus tungro menyebabkan malai
pendek, gabah tidak terisi sempurna atau kebanyakan hampa dan terdapat bercak-bercak
coklat yang menutupi malai (Ling, 1972).
F. Epidemi Penyakit
1. Siklus penyakit
Masa inkubasi dalam tanaman adalah 6 – 9
hari. Infeksi tungro dapat terjadi mulai persemaian.
Pada stadium ini tanaman sangat rentan terhadap
infeksi virus. Apabila infeksi terjadi pada stadium
persemaian maka gejala tungro akan terlihat pada
tanaman umur 2-3 minggu setelah tanam (mst).
Tanaman muda yang terinfeksi merupakan sumber
infeksi di lapangan. Serangga dapat menularkan
virus dengan segera dalam waktu 2 jam setelah memperoleh virus dan mempertahankan
dalam tubuhnya selama tidak lebih dari 5 hari. Setelah masa itu, serangga menjadi
tidak infektif lagi. Kembali menjadi infektif setelah menghisap tanaman sakit.
2

2. Penyebaran penyakit
Menularkan penyakit secara non persisten. Nimfa wereng hijau dapat
menularkan virus, tetapi infektif setelah ganti kulit. Virus tidak dapat ditularkan
melalui telur serangga maupun melalui biji, tanah, air dan secara mekanis.
3. Faktor-faktor lingkungan yang mendukung
Populasi wereng hijau pada musim kemarau lebih rendah dari pada musim hujan
(Carino, 1980). Keberadaan wereng hijau sangat dipengaruhi oleh iklim terutama suhu
yang berpengaruh terhadap daur hidup wereng hijau. Curah hujan dan kelembaban
relatif berpengaruh terhadap dinamika populasi wereng hijau (Siwi et al., 1987).
Peningkatan intensitas serangan tungro seiring dengan meningkatnya populasi vektor
infektif di lapangan.
4. Cara bertahan patogen
Penyakit tungro akan tetap ada walaupun sudah di cegah. Karena patogen tungro
dapat bertahan hidup pada organisme lain seperti wereng hijau.
G. Pengendalian
1. Waktu Tanam Tepat
Waktu tanam berhubungan erat dengan pola fluktuasi populasi wereng hijau.
Waktu tanam tepat diidentifikasi berdasarkan pola fluktuasi populasi wereng hijau,
keberadaan virus tungro dan curah hujan. Pola fluktuasi populasi wereng hijau di suatu
tempat akan berbeda dari musim ke musim tergantung keadaan curah hujan sehingga
akan terjadi puncak populasi pada waktu atau bulan tertentu (Sogawa, 1976). Tingginya
serangan tungro dapat disebabkan oleh tingginya tekanan vektor. Semakin tinggi
populasi vektor maka semakin tinggi intensitas serangan tungro (Tiongco et al., 1983).
3

Pada saat populasi wereng hijau tinggi, pertanaman telah masuk fase generatif sehingga
mengurangi tekanan infeksi virus (Hasanuddin, 2002)
2. Penggunaan Varietas Tahan
Komponen yang paling penting dan mudah di lakukan dalam strategi
pengendalian tungro adalah penggunaan varietas tahan (Sama, 1985), bahkan paling
efektif dalam usaha pengendalian tungro pada berbagai ekosistem di Indonesia
(Daradjat et al., 1999). Ketahanan varietas terhadap virus tungro akan menekan
intensitas serangan dan ketahanan terhadap vektor akan menekan penularan tungro.
Peningkatan proporsi varietas tahan di suatu hamparan berpengaruh nyata dalam
mengurangi keberadaan tungro (Holt, 1996).
Beberapa varietas tahan virus tungro dan wereng hijau telah dilepas untuk
mengendalikan tungro seperti Tukad Unda, Tukad Petanu, Tukad Balian, Kalimas dan
Bondoyudo (Daradjat et al., 2004). Namun ketahanan varietas bersifat spesifik lokasi
yang berarti bahwa suatu varietas menunjukkan tahan terhadap strain virus di daerah
tertentu tetapi tidak tahan terhadap strain virus di daerah lain (Baehaki dan Suharto,
1985).
3. Pergiliran Varietas
Pergiliran varietas tahan akan memperpanjang durasi ketahanan varietas dan
mengurangi tekanan seleksi wereng hijau. Pergiliran varietas memerlukan informasi
tingkat adaptasi wereng hijau terhadap varietas tahan (Widiarta et al., 2004). Varietas
tahan tidak boleh ditanam terus-menerus karena dapat meningkatkan tekanan seleksi
vektor dan memungkinkan berkembangnya wereng hijau biotipe baru (Sama, 1985;
Daradjat et al., 1999). Koloni wereng hijau sangat mudah beradaptasi terhadap varietas
tahan bila telah berhasil terbentuk hingga enam generasi (Siwi dan Suzuki, 1991),
bahkan dapat terjadi setelah generasi ke-3 dan generasi selanjutnya, khususnya generasi
ke-6, aspek biologi wereng hijau tidak berbeda nyata apabila berada dalam varietas
peka (Taulu et al., 1987). Telah dilaporkan pula bahwa durasi ketahanan varietas
terhadap wereng hijau sekitar 2 generasi siklus hidup wereng hijau (Heinrich et al.,
1982).
4. Kultur Teknis
Pengelolaan tanaman terpadu dalam pengendalian tungro meliputi beberapa
komponen yaitu tanam serempak, sebar benih sebelum puncak kepadatan populasi
wereng hijau, sebar benih setelah lahan dibersihkan, tanam dengan cara legowo dan
manipulasi faktor lingkungan (Muis et al., 1990). Vektor dewasa pada pola tanam tidak
4

serempak lebih aktif memencar dibandingkan pada pola tanam serempak (Aryawan et
al., 1993 dalam Widiarta et al., 2004).
Penanaman dengan cara legowo dua baris atau empat baris dapat menekan
pemencaran wereng hijau. Mengatur ketersediaan air merupakan bentuk manipulasi
lingkungan yang mempengaruhi penyebaran tungro. Kondisi pertanaman yang kering
akan merangsang pemencaran wereng hijau yang akan memperluas penyebaran tungro
(Widiarta et al., 2004).
5. Penggunaan Insektisida
Penggunaan insektisida dalam mengendalikan tungro bertujuan untuk eradikasi
vektor pada pertanaman yang terserang tungro agar tidak menyebar ke pertanaman lain
dan mencegah terjadinya infeksi virus pada pertanaman sehat. Insektisida sistemik
bentuk butiran lebih efektif dalam mencegah infeksi tungro oleh vektor seperti
carbofuran, aminosulfan dan UC54229 (Habibuddin et al., 1987). Insektisida
imidacloprit atau tiametoksan dapat digunakan pada persemaian untuk manghambat
penularan tungro oleh vektor. Penggunaan insektisida hayati dengan jamur
entomopatogen diketahui dapat mengurangi dan menekan pemencaran vektor. Jamur
Beauveria bassiana dan Metharizium anisopliae dapat menekan pemencaran dan
menyebabkan mortalitas vektor dengan masa inkubasi yang berbeda (Widiarta et al.,
2004). Aplikasi insektisida pada satu hari setelah tanam (HST) dan 30 HST dapat
mengendalikan populasi wereng hijau dan mengurangi intensitas serangan tungro
(Manwan et al., 1987).
5

DAFTAR PUSTAKA
Agrios GN (1997). Plant pathology, 4th ed. Academic Press. Dan Diego, CA. 635 pp.Baehaki, S.E. dan H. Suharto. 1985. Penyakit Tungro. Makalah temu lapang pengendalian penyakit
tungro di Banyumas, 18-19 September 1985.Carino, F. O. 1980. Role of natural enemies in population suppression and pest management of the
green leaf hopper. UPLB. MS. Thesis.Daradjat, A. A., I.N. Widiarta dan A. Hasanuddin. 1999. Breeding for rice tungro virus resistance in
Indonesia. Rice Tungro Disease Management. IRRI.Daradjat, A. A., I.N. Widiarta dan Jumanto. 2004. Prospek perbaikan varietas padi tahan virus tungro
dan serangga wereng hijau. Prosiding Seminar Nasional Status Program Penelitian Tungro Mendukung Keberlanjutan Produksi Padi Nasional. Makassar, 7-8 September 2004. Puslitbang Tanaman Pangan.
Habibuddin, H., T. Takita and N.K. Ho. 1987. Research and management of tungro disease in Peninsular Malaysia. In Proc.of the workshop on rice tungro virus. Ministry of Agriculture. AARD-Maros Research Institute for Food Crops.
Hasanuddin, A. 2002. Pengendalian penyakit tungro terpadu : Strategi dan implementasi. Orasi pengukuhan Ahli Peneliti Utama. Puslitbang Tanaman Pangan. Badan Litbang Pertanian.
Heinrichs, E.A., F. Madrano, L. Sunio, H. Rapusas, A. Romena, C. Vega, V. Viajante, D. Centina and T. Domingo. 1982. Resistance of IR varieties to insect. Int. Rice Res. Newsl. 7: 9-10.
Heru R. Praptana. 2005. Penyakit Tungro dan Pengendaliannya. Loka Penelitian Penyakit Tungro Lanrang.
Holt, J. 1996. Spatial medelling of rice tungro disease epidemics. In. Rice Tungro Disease Epidemiology and Vector Ecology. eds. Chancellor, Teng and Heong, IRRI and NRI, 74-86.
Hibino H., M. Roechan and S. Sudarsman, 1978. Association of two types of virus particles with Penyakit Habang (Tungro disease) of rice in Indonesia. Phytopathol. 68: 1412-16.
Hull R. 1996. Molecular biology of rice tungro viruses. Annu. Rev. Phytopathol. 34:275-297.Ling, K.C. 1976. recent studies on Rice Tungro Disease at IRRI. Research Paper Series. No. 1.Manwan, I., S. Sama and S. A. Rizvi. 1987. Management strategy to control rice tungro in Indonesia.
In Proc. of the workshop on rice tungro virus. Ministry of Agriculture. AARD-Maros Research Institute for Food Crops. 92-97p.
Muis, A., M. Yasin, S. dan A. Hasanuddin. 1990. Epidemiologi penyakit tungro, pergiliran varietas dan waktu tanam. Hasil Penelitian Padi, Balai Penelitian Tanaman Pangan Maros, 1990, (1): 47-52.
Sama, S. 1985. Penerapan konsep pergiliran varietas dalam pengelolaan penyakit tungro. Makalah temu lapang pengendalian penyakit tungro di Banyumas, 18-19 September 1985.
Siwi, S.S. dan Y. Suzuki. 1991. The green leafhopper (Nephotettix spp.): vector of rice tungro virus disease in Southeast Asia, particularly in Indonesia and its management. Indonesian Agricultural Research & Development. Journal.Vol. 13.
Sogawa, K. 1976. Rice tungro virus and its vectors in tropical Asia. Rev. Plant Protec. 9. p. 25-46
Taulu, L.A., S. Sosromarsono, I.N. Oka and E. Guhardja. 1987. Adaptation of green leafhopper, Nephotettix virescens (Distant) to several varieties of rice. Proceeding of the Workshop on Rice Tungro Virus. AARD – Maros Research Insitute for Food Crops. p: 56-62.
Tiongco, E.R., R.C. Cabunagan and H. Hibino. 1983. Resistance of five IR varieties to tungro. Int. Rice. Res. Newsl. 8(4): 6
Widiarta, I.N., D. Kusdiaman dan A. Hasanuddin. 2003. Pemencaran wereng hijau dan keberadaan tungro pada pertanaman padi dengan beberapa cara tanam. Penelitian Pertanian tanaman Pangan. 22(3): 129-133
Widiarta, I.N., Burhanuddin, A.A. Daradjat dan A. Hasanuddin. 2004. Status dan Program Penelitian Pengendalian Terpadu Penyakit Tungro. Prosiding Seminar Nasional Status Program Penelitian Tungro Mendukung Keberlanjutan Produksi Padi Nasional. Makassar, 7-8 September 2004.
6

A. NAMA PENYAKIT :Layu Sclerotium
B. INANG : Kedelai
C. ARTI PENTING PENYAKIT
Kelayuan dapat terjadi pada tanaman stadia vegetatif hingga stadia generatif. Gejala
ketika kecambah belum muncul di permukaan tanah disebut preemergence damping-off
dan ketika kecambah sudah muncul di permukaan tanah disebut postemergence damping-
off. Penyakit ini sangat berbahaya jika terjadi pada biji kedelai di penyimpanan atau dalam
pengiriman, karena satu dapat berkembang pada biji yang masih sehat. Penyebab layu ini
adalah cendawan Sclerotium rolfsii (Semangun, 1991). Sclerotium rolfsii merupakan salah
satu jamur patogen yang menyebabkan beberapa penyakit pada tanaman, seperti busuk
batang, layu serta rebah kecambah.
D. PATOGEN
1. Morfologi
Cendawan S. rolfsii membentuk miselium tipis, berwarna putih, teratur seperti
bulu ayam (Agrios, 2005). S. rolfsii mampu bertahan dalam tanah dengan membentuk
struktur bertahan berupa sklerotia. Sklerotia merupakan kumpulan miselia cendawan
yang memampat, berbentuk butiran keras dengan diameter sekitar 1-2 mm berwarna
kecoklatan, dan mampu bertahan lama di dalam tanah dan residu tanaman. Sklerotia
mampu bertahan dalam tanah dalam waktu yang cukup lama dari 2 tahun hingga 10
tahun (Messiaen, 1994). Sklerotia terdiri atas tiga lapisan, yaitu kulit dalam, kulit luar,
dan kulit teras. Pada kulit dalam terdapat 6–8 lapisan sel, kulit luar 4–6 lapisan sel,
sedangkan kulit teras terdiri atas benang-benang hifa yang hialin dan tidak mengalami
penebalan dinding sel (Chet et al. 1969).
2. Klasifikasi
Kingdom: Fungi
Phylum: Basidiomycota
Class: Agaricomycetes
Order: Atheliales
Family: Atheliaceae
Genus: Athelia
Species: Athelia rolfsii Synonym Sclerotium roflsii anamorph sacc
7

3. Sifat Patogen
Sclerotium rolfsii merupakan salah satu jamur patogen yang dapat menyebabkan
beberapa penyakit mematikan pada tanaman seperti busuk batang, layu dan rebah
kecambah. Patogen ini merupakan penyebab penyakit potensial pada tanaman kedelai,
karena langsung menyerang pada jaringan tanaman dengan memproduksi miselium
yang berlimpah dan menghancurkannya dengan mensekresi asam oksalis, pektinolitik,
selulolitik, dan enzim lain setelah penetrasi pada jaringan inang (Agrios, 2005).
E. Gejala penyakit
Infeksi S. rolfsii pada kedelai biasanya mulai terjadi di
awal pertumbuhan tanaman dengan gejala busuk kecambah
atau rebah semai. Pada tanaman kedelai berumur lebih dari 2-3
minggu, gejalanya berupa busuk pangkal batang dan layu,
pada bagian terinfeksi terlihat bercak berwarna coklat pucat
dan di bagian tersebut tumbuh miselia cendawan berwarna
putih (Punja, 1988). Tanda yang paling mudah dikenali dari
penyakit ini adalah adanya miselium cendawan berwarna putih seperti bulu pada pangkal
batang yang sakit atau pada permukaan tanah.
F. Epidemi Penyakit
1. Siklus Penyakit
Seperti cendawan yang lain, S. rolfsii juga mempunyai hifa, tetapi hifanya tidak
membentuk spora melainkan sklerotia, sehingga identifikasinya didasarkan atas
karakteristik, ukuran, bentuk, dan warna sklerotia. Pada media buatan, sklerotia baru
terbentuk setelah 8–11 hari.
2. Penyebaran Penyakit
Penyebran penyakit oleh cendawan Sclerotium biasanya melalui medium tanah
(soil borne) yang sering disebut cendawan tular tanah karena dapat bertahan di tanah.
Di samping itu, jamur tersebut dapat menyebar melalui air irigasi dan benih pada lahan
yang ditanami secara terus menerus dengan tanaman inang dari Sclerotium rolfsii
tersebut, sehingga mengakibatkan turunnya produksi tanaman yang akan dipanen
(Timper et al. 2001).
3. Faktor Faktor lingkungan yang mendukung
8

Pada kelembapan yang tinggi, infeksi S. rolfsii pada tanaman semakin meningkat.
Sebaliknya jika kelembapan berkurang, intensitas dan luas serangan penyakit berkurang
dan miselium akan membentuk sklerotia. Pada medium buatan, sklerotia akan
berkecambah pada kisaran kelembapan 25–30% (Domsch et al., 1980).Cendawan S.
rolfsii berkembang dengan baik pada kisaran pH 3,5–6,0 (Domsch et al., 1980), namun
peneliti lain menyatakan pertumbuhan optimum miselium cendawan ini berada pada
kisaran pH 1,4–2,0. Perkecambahan sklerotium yang optimum terjadi pada kisaran suhu
21−30°C. Pada suhu 0°C, hifa akan mati dan tidak dapat membentuk sklerotium, dan
pada suhu -10°C sklerotium akan mati (Domsch et al.,1980).
4. Cara bertahan hidup
Cendawan Sclerotium bertahan hidup di dalam tanah atau sisa-sisa tanaman
dalam bentuk hifa atau sklerotia sebagai mikroorganisme yang bersifat parasit
fakultatif. Sklerotia mampu bertahan dalam tanah dalam waktu yang cukup lama dari 2
tahun hingga 10 tahun (Messiaen, 1994). Cendawan tersebut akan hidup sebagai
saprofit apabila tidak dijumpai tanaman inang. Mikroorganisme yang demikian
mempunyai kemampuan aktivitas kompetisi saprofit yang rendah.
G. PENGENDALIAN
Pengendalian penyakit tular tanah sebaiknya disesuaikan dengan cara bertahan hidup
cendawan. Cara pengendalian penyakit yang dapat diterapkan adalah aplikasi
mikroorganisme antagonisnya, penggunaan varietas tahan, dan cara mekanis. Rotasi
tanaman sulit dilakukan karena kisaran tanaman inangnya sangat luas. Pengendalian
dengan fungisida kimiawi tidak tepat karena penggunaannya harus sering sesuai dengan
sifat tanah yang menyerap, selain dapat mencemari lingkungan dan mematikan musuh
alami dan mikroorganisme pendegradasi senyawa kimia beracun. Selain itu, fungisida
dapat mencemari air tanah dan berdampak buruk bagi kesehatan penduduk sekitar. Cara
pengendalian penyakit yang sering dilakukan adalah dengan mencabut tanaman yang
sakit. Cara ini dapat diteruskan jika jumlah tanaman yang terserang dalam suatu area
pertanaman hanya sedikit. Tanaman yang telah dicabut harus segera dibenamkan ke dalam
tanah atau dibakar supaya tidak menular. Di Hawai, pengendalian S. rolfsii dilakukan
dengan memadukan kultur teknis, rotasi tanaman, pengolahan tanah lebih dari 20 cm,
pemberian kompos, solarisasi tanah, mulsa plastik hitam, pengendalian hayati dengan
memanfaatkan antagonisnya, dan penggunaan fungisida (Ferreira dan Boyle, 2006)
9

DAFTAR PUSTAKA
Agrios, ON. 2005. Plant Pathology. Edisi ke-5. New York: Academic Pr.
Chet, I., Y. Henis, and Kislev. 1969. Ultrastructure of sclerotia and hyphae of Sclerotium
rolfsii Sacc. Gen. Microbiol. 57: 143–147.
Domsch, K.H., W. Gams, and T.H. Anderson. 1980. Compendium of Soil Fungi (Vol. 1).
Academic Press, London.
Ferreira, S.A. and R.A. Boyle. 2006. Sclerotium rolfsii. Department of Plant Pathology,
University of Hawaii at Manoa.
Messiaen, CM. 1994. The Tropical Vegetable Garden. London: CTA Macmillan Press Ltd.
Pp. 441-442.
Punja, ZK. 1988. Sclerotium (Athelia) rolfsii, a pathogen of many plant species. Di dalam :
Sidhu GS, editor. Genetic of Plant Pathogenic Fungi. London: Academic Press. 16:
523-534.
Semangun, H. 1993. Penyakit-penyakit Tanaman Pangan di Indonesia. Gadjah Mada
University Press, Yogyakarta.
Timper P, Minton NA, Johnson AW, Brenneman TB, Culbrreat AK, Burton GW, Baker SH,
Gascho GJ (2001) Influence of cropping system on stem rot (Sclerotium rolfsii),
Meloydogyne arenaria, and the nematode antagonist Pasteuria penetrans in peanut.
Plant Disease. 85: 767-772.
10