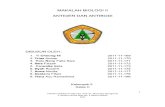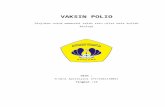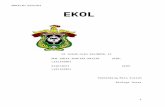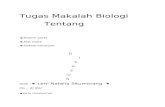MAKALAH BIOLOGI
-
Upload
puspa-dewy-saputra -
Category
Documents
-
view
211 -
download
0
Transcript of MAKALAH BIOLOGI
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Systemic lupus erytematosus (SLE) atau lupus eritematosus sistemik (LES) adalah penyakit radang atau inflamasi multisistem yang penyebabnya diduga karena adanya perubahan sistem imun (Albar, 2003). SLE termasuk penyakitcollagenvascular yaitu suatu kelompok penyakit yang melibatkan sistem muskuloskeletal, kulit, dan pembuluh darah yang mempunyai banyak manifestasi klinik sehingga diperlukan.
pengobatan yang kompleks. Etiologi dari beberapa penyakit collagen-vascular sering tidak diketahui tetapi sistem imun terlibat sebagai mediator terjadinya penyakit tersebut (Delafuente, 2002). Berbeda dengan HIV/AIDS, SLE adalah suatu penyakit yang ditandai dengan peningkatan sistem kekebalan tubuh sehingga antibodi yang seharusnya ditujukan untuk melawan bakteri maupun virus yang masuk ke dalam tubuh berbalik merusak organ tubuh itu sendiri seperti ginjal, hati, sendi, sel darah merah, leukosit, atau trombosit. Karena organ tubuh yang diserang bisa berbeda antara penderita satu dengan lainnya, maka gejala yang tampak sering berbeda, misalnya akibat kerusakan di ginjal terjadi bengkak pada kaki dan perut, anemia berat, dan jumlah trombosit yang sangat rendah (Sukmana, 2004). Penderita SLE diperkirakan mencapai 5 juta orang di seluruh dunia (Yayasan Lupus Indonesia). Prevalensi pada berbagai populasi berbeda-beda bervariasi antara 3 400 orang per 100.000 penduduk (Albar, 2003). SLE lebih sering ditemukan pada ras-ras tertentu seperti bangsa Afrika Amerika, Cina, dan mungkin juga Filipina. Di Amerika, prevalensi SLE kira-kira 1 kasus per 2000 populasi dan insiden berkisar 1 kasus per 10.000 populasi (Bartels, 2006). Prevalensi penderita SLE di Cina adalah 1 :1000 (Isenberg and Horsfall,1998). Meskipun bangsa Afrika yang hidup di Amerika mempunyai prevalensi yang tinggi terhadap SLE, penyakit ini ternyata sangat jarang ditemukan pada orang kulit hitam yang hidup di Afrika. Di Inggris, SLE mempunyai prevalensi 12 kasus per 100.000 populasi, sedangkan di Swedia 39 kasus per 100.000 populasi. Di New Zealand, prevalensi penyakit ini pada Polynesian sebanyak 50 kasus per 100.000 populasi dan hanya 14,6 kasus per 100.000 populasi pada orang kulit putih (Bartels, 2006). Di Indonesia sendiri jumlah penderita SLE secara tepat belum diketahui tetapi diperkirakan sama dengan jumlah penderita SLE di Amerika yaitu 1.500.000 orang (Yayasan Lupus Indonesia). Berdasarkan hasil survey, data morbiditas penderita SLE di RSU Dr. Soetomo Surabaya selama tahun 2005 sebanyak 81 orang dan prevalensi penyakit ini menempati urutan keempat setelah osteoartritis, reumatoid artritis, dan low
back pain. Di RSU Dr. Saiful Anwar Malang, penderita SLE pada bulan Januari sampai dengan Agustus 2006 ada 14 orang dengan 1 orang meninggal dunia. Setiap tahun ditemukan lebih dari 100.000 penderita baru. Hal ini disebabkan oleh manifestasi penyakit yang sering terlambat diketahui sehingga berakibat pada pemberian terapi yang inadekuat, penurunan kualitas pelayanan, dan peningkatan masalah yang dihadapi oleh penderita SLE. Masalah lain yang timbul adalah belum terpenuhinya kebutuhan penderita SLE dan keluarganya tentang informasi, pendidikan, dan dukungan yang terkait dengan SLE. Oleh karena itu penting sekali meningkatkan kewaspadaan masyarakat tentang dampak buruk penyakit SLE terhadap kesehatan serta dampak psikologi dan sosialnya yang cukup berat untuk penderita maupun keluarganya. Kurangnya prioritas di bidang penelitian medik untuk menemukan obat-obat penyakit SLE yang baru, aman dan efektif, dibandingkan dengan penyakit lain juga merupakan masalah tersendiri (Yayasan Lupus Indonesia). Manifestasi klinis dari SLE bermacam-macam meliputi sistemik, muskuloskeletal, kulit, hematologik, neurologik, kardiopulmonal, ginjal, saluran cerna, mata, trombosis, dan kematian janin (Hahn, 2005). Penderita SLE dengan manifestasi kulit dan muskuloskeletal mempunyaisurvival rate yang lebih tinggi daripada dengan manifestasi klinik renal dancentral nervous system (CNS). Meskipun mempunyai survival rate yang berbeda, penderita dengan SLE mempunyai angka kematian tiga kali lebih tinggi dibandingkan orang sehat. Saat ini prevalensi penderita yang dapat mencapai survival rate 10 tahun mendekati 90%, dimana pada tahun 1955 survival rate penderita yang mencapai 5 tahun kurang dari 50%. Peningkatan angka ini menunjukkan peningkatan pelayanan terhadap penderita SLE yang berkaitan dengan deteksi yang lebih dini, perawatan dan terapi yang benar sejalan dengan perkembangan ilmu kedokteran dan farmasi. Penyebab mortalitas paling tinggi terjadi pada awal perjalanan penyakit SLE adalah infeksi yang disebabkan oleh pemakaian imunosupresan. Sedangkan mortalitas pada penderita SLE dengan komplikasi nefritis paling banyak ditemukan dalam 5 tahun pertama ketika dimulainya gejala. Penyakit jantung dan kanker yang berkaitan dengan inflamasi kronik dan terapi sitotoksik juga merupakan penyebab mortalitas. The Framingham Offspring Study menunjukkan bahwa wanita dengan usia 35 44 tahun yang menderita SLE mempunyai resiko 50 kali lipat lebih besar untuk terkena infarct miocard daripada wanita sehat. Penyebab peningkatan penyakit coronary artery disease (CAD) merupakan multifaktor termasuk disfungsi endotelial, mediator inflamasi, kortikosteroid yang menginduksi arterogenesis, dan dislipidemia yang berkaitan dengan penyakit ginjal (salah satu manifestasi klinis dari SLE). Dari suatu hasil penelitian menunjukkan penyebab mortalitas 144 dari 408 pasien dengan SLE yang dimonitor lebih
dari 11 tahun adalah lupus yang akif (34%), infeksi (22%), penyakit jantung (16%), dan kanker (6%) (Bartels, 2006). Penderita dengan SLE membutuhkan pengobatan dan perawatan yang tepat dan benar. Pengobatan pada penderita SLE ditujukan untuk mengatasi gejala dan induksi remisi serta mempertahankan remisi selama mungkin pada perkembangan penyakit. Karena manifestasi klinis yang sangat bervariasi maka pengobatan didasarkan pada manifestasi yang muncul pada masing-masing individu. Obat-obat yang umum digunakan pada terapi farmakologis penderita SLE yaitu NSAID (Non-Steroid Anti-Inflammatory Drugs), obat-obat antimalaria, kortikosteroid, dan obat-obat antikanker (imunosupresan) selain itu terdapat obat-obat yang lain seperti terapi hormon, imunoglobulin intravena, UV A-1 fototerapi, monoklonal antibodi, dan transplantasi sumsum tulang yang masih menjadi penelitian para ilmuwan. NSAID dapat digunakan untuk SLE ringan. Dosis yang digunakan harus memadai untuk menimbulkan efek antiinflamasi. Aspirin dosis rendah dapat digunakan pada pasien dengan sindrom antifosfolipid. Penggunaan NSAID dapat menyebabkan penurunan fungsi ginjal, hal ini dapat memperparah terjadinya lupus nefritis (Delafuente, 2002). Obat antimalaria seperti klorokuin dan hidroklorokuin dapat digunakan untuk mengatasi lupus dengan lesi kulit berbentuk cakram. Selain itu obat ini juga dapat digunakan untuk terapi SLE terutama pada pasien dengan keluhan manifestasi kulit, pleuritis, inflamasi perikardial ringan, anemia ringan dan leukopenia. Obat ini digunakan umumnya dalam jangka panjang. Selain NSAID dan antimalaria, kortikosteroid juga digunakan pada terapi SLE. Penderita SLE tidak selalu memerlukan kortikosteroid, pasien dengan manifestasi klinis yang serius dan tidak memberikan respon terhadap penggunaan obat lain baru diberikan terapi kortikosteroid. Beberapa pasien yang mengalami lupus eritematosus pada kulit baik kronik atau subakut lebih menguntungkan jika diberikan kortikosteroid topikal atau intralesional. Tujuan pemberian kortikosteroid adalah untuk menekan penyakit yang aktif dan mempertahankannya dengan dosis serendah mungkin. Terapi kortikosteroid yang diberikan jangka pendek dan dosis tinggi intravena mempunyai tujuan yaitu untuk menginduksi terjadinya remisi pada penderita SLE yang mempunyai manifestasi klinik serius. Untuk obat-obat sitotoksik yang digunakan adalah kategori bahan pengalkilasi seperti siklofosfamid dan antimetabolit azatioprin. Biasanya obat-obat tersebut dikombinasikan dengan kortikosteroid. Tujuan kombinasi ini adalah untuk mengurangi dosis steroid dan meningkatkan efektivitas steroid (Delafuente, 2002). Selain obat-obat yang digunakan untuk pengobatan penyakit SLE, perlu juga diwaspadai obatobat yang dapat menginduksi terjadinya penyakit SLE antara lain hidralazin, prokainamid, metildopa, klorpromazin, dll. (Herfindal et al., 2000).
Oleh karena itu sejalan dengan perkembangan ilmu terapi dan perubahan paradigma kefarmasian ke arah pharmaceutical care, farmasis sebaiknya turut berperan dalam tim kesehatan dalam hal pemilihan obat, penyediaan produk obat, monitor efek obat, mengidentifikasi problema obat yang maupun yang berpotensi untuk timbul serta pengobatan kompleks yang diberikan kepada penderita SLE. Hal ini penting mengingat SLE adalah penyakit dengan banyaknya manifestasi klinik yang muncul maka diperlukan penguasaan yang baik mengenai penggunaan obat di lapangan yang data-datanya dapat diperoleh melalui studi penggunaan obat. Berdasarkan latar belakang tersebut, dilakukan penelitian untuk mempelajari pola penggunaan obat pada penderita SLE sehingga dapat diketahui bahwa terapi yang diberikan tepat dan adekuat serta dapat meningkatkan kualitas hidup pasien.
B. RUMUSAN MASALAH Apakah penyakit lupus itu? Seberapa besar bahaya penyakit lupus itu? Apa gejala dari penyakit lupus? Bagaimana cara penyembuhan penyakit lupus?
C. TUJUAN Pembuatan makalah ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan tentang penyakit lupus, terutama dalam segi gejala, cara penyembuhan. Menerangkan manfaat dari sistem ini bukan hanya untuk menolong penderita lupus bertahan hidup tapi juga memiliki semangat yang baru. Untuk mengetahui pengertian penyakit Sistemic Lupus Erythematosus. Untuk mengetahui etiologi penyakit Sistemic Lupus Erythematosus. Untuk mengetahui klasifikasi penyakit Sistemic Lupus Erythematosus. Untuk mengetahui patofisiologi penyakit Sistemic Lupus Erythematosus. Untuk mengetahui gejala klinis penyakit Sistemic Lupus Erythematosus. Untuk mengetahui manipestasi klinis penyakit Sistemic Lupus Erythematosus. Untuk mengetahui bagaimana menegakkan diagnosis enyakit Sistemic Lupus Erythematosus. Untuk mengetahui apa resiko yang ditimbulkan dari penyakit Sistemic Lupus Erythematosus Untuk mengetahui bagaimana penatalaksanaan penyakit Sistemic Lupus Erythematosus
D. MANFAAT
Makalah ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pola penggunaan obat pada pasien SLE sehingga mampu memberikan pelayanan terapi obat secara optimal pada penderita.
BAB II PEMBAHASAN A. PENGERTIAN
SLE (Systemisc Lupus erythematosus) adalah penyakit autoimun dimana organ dan sel mengalami kerusakan yang disebabkan oleh tissuebinding autoantibody dan kompleks imun, yang menimbulkan peradangan dan bisa menyerang berbagai sistem organ namun sebabnya belum diketahui secara pasti, dengan perjalanan penyakit yang mungkin akut dan fulminan atau kronik, terdapat remisi dan eksaserbasi disertai oleh terdapatnya berbagai macam autoantibody dalam tubuh. Pada setiap penderita, peradangan akan mengenai jaringan dan organ yang berbeda. Beratnya penyakit bervariasi mulai dari penyakit yang ringan sampaI penyakit yang menimbulkan kecacatan, tergantung dari jumlah dan jenis antibodi yang muncul dan organ yang terkena.
1. Etiologi
Penyakit SLE terjadi akibat terganggunya regulasi kekebalan yang menyebabkan peningkatan autoantibody yang berlebihan. Gangguan imunoregulasi ini ditimbulkan oleh kombinasi antara faktor-faktor genetik, hormonal (sebagaimana terbukti oleh awitan penyakit yang biasanya terjadi selama usia reproduktif) dan lingkungan (cahaya matahari, luka bakar termal).
Sampai saat ini penyebab SLE belum diketahui. Diduga faktor genetik, infeksI dan lingkungan ikut berperan pada patofisiologi SLE. Sistem imun tubuh kehilangan kemampuan untuk membedakan antigen dari sel dan jaringan tubuh sendiri. Penyimpangan reaksi imunologi ini akan dalam pembentukan kompleks imun sehingga mencetuskan penyakit inflamasi imun sistemik dengan kerusakkan multiorgan. Dalam keadaan normal, sistem kekebalan berfungsi mengendalikan pertahanan tubuh dalam melawan infeksi. Pada lupus dan penyakit autoimun lainnya, sistem pertahanan tubuh ini berbalik melawan tubuh, dimana antibodi yang dihasilkan menyerang sel tubuhnya sendiri. Antibodi ini menyerang sel darah, organ dan jaringan tubuh, sehingga terjadi penyakit menahun. Mekanisme maupun penyebab dari penyakit autoimun ini belum sepenuhnya dimengerti tetapi diduga melibatkan faktor lingkungan dan keturunan. Beberapa faktor lingkungan yang dapat memicu timbulnya lupus: Infeksi Antibiotik (terutama golongan sulfa dan penisilin) Sinar ultraviolet Stres yang berlebihan Obat-obatan tertentu Hormon. Meskipun lupus diketahui merupakan penyakit keturunan, tetapi gen penyebabnya tidak diketahui. Penemuan terakhir menyebutkan tentang gen dari kromosom 1. Hanya 10% dari penderita yang memiliki kerabat (orang tua maupun saudara kandung) yang telah maupun akan menderita lupus. Statistik menunjukkan bahwa hanya sekitar 5% anak dari penderita lupus yang akan menderita penyakit ini. Lupus seringkali disebut sebagai penyakit wanita walaupun juga bisa diderita oleh pria. Lupus bisa menyerang usia berapapun, baik pada priamaupun wanita, meskipun 10-15 kali lebih sering ditemukan pada wanita. Faktor hormonal mungkin bisa menjelaskan mengapa lupus lebih sering menyerang wanita. Meningkatnya gejala penyakit ini pada masa sebelum menstruasi dan/atau selama kehamilan mendukung keyakinan bahwa hormon (terutama estrogen) mungkin berperan dalam timbulnya penyakit ini. Meskipun demikian, penyebab yang pasti dari lebih tingginya angka kejadian pada wanita dan pada masa pra-menstruasi, masih belum diketahui.
a. Faktor Resiko terjadinya SLE 1. Faktor Genetik Jenis kelamin, frekuensi pada wanita dewasa 8 kali lebih sering daripada pria dewasa Umur, biasanya lebih sering terjadi pada usia 20-40 tahun Etnik, Faktor keturunan, dengan Frekuensi 20 kali lebih sering dalam keluarga yang terdapat anggota dengan penyakit tersebut 2. Faktor Resiko Hormon Hormon estrogen menambah resiko SLE, sedangkan androgen mengurangi resiko ini. 3. Sinar UV Sinar Ultra violet mengurangi supresi imun sehingga terapi menjadi kurang efektif, sehingga SLE kambuh atau bertambah berat. Ini disebabkan sel kulit mengeluarkan sitokin dan prostaglandin sehingga terjadi inflamasi di tempat tersebut maupun secara sistemik melalui peredaran pembuluh darah 4. Imunitas Pada pasien SLE, terdapat hiperaktivitas sel B atau intoleransi terhadap sel T 5. Obat Obat tertentu dalam presentase kecil sekali pada pasien tertentu dan diminum dalam jangka waktu tertentu dapat mencetuskan lupus obat (Drug Induced Lupus Erythematosus atau DILE). Jenis obat yang dapat menyebabkan Lupus Obat adalah : Obat yang pasti menyebabkan Lupus obat : Kloropromazin, metildopa, hidralasin, prokainamid, dan isoniazid Obat yang mungkin menyebabkan Lupus obat : dilantin, penisilamin, dan kuinidin Hubungannya belum jelas : garam emas, beberapa jenis antibiotic dan griseofurvin 6. Infeksi Pasien SLE cenderung mudah mendapat infeksi dan kadang-kadang penyakit ini kambuh setelah infeksi 7. Stres Stres berat dapat mencetuskan SLE pada pasien yang sudah memiliki kecendrungan akan penyakit ini.Faktor penyebab terserangnya seseorang terhadap penyakit Lupus hingga kini belum diketahui, tetapi pengaruh lingkungan dan faktor genetik, hormon diduga sebagai penyebabnya. Faktor Genetik : Tidak diketahui gen atau gen gen apa yang menjadi penyebab penyakit tersebut, 10% dalam keluarga Lupus mempunyai keluarga dekat orang tua atau kaka adik) yang juga menderita lupus, 5% bayi yang dilahirkan dari penderita lupus terkena lupus juga, bila kembar identik, kemungkinan yang terkena Lupus hanya salah satu dari kembar tersebut. Faktor lingkungan sangat berperan sebagai pemicu Lupus, misalnya : infeksi, stress, makanan, antibiotik (khususnya kelompok sulfa dan penisilin), cahaya ultra violet (matahari) dan penggunaan obat obat tertentu. Faktor hormon, dapat menjelaskan mengapa kaum perempuan lebih sering terkena penyakit lupus dibandingkan dengan laki-laki. Meningkatnya angka pertumbuhan penyakit Lupus sebelum periode menstruasi atau selama masa kehamilan mendukung keyakinan bahwa hormon, khususnya ekstrogen menjadi penyebab pencetus penyakit Lupus. Akan tetapi hingga kini belum diketahui jenis hormon apa yang menjadi penyebab besarnya prevalensi lupus pada perempuan pada periode tertentu yang menyebabkan meningkatnya gejala Lupus masih belum diketahui. Faktor sinar matahari adalah salah satu kondisi yang dapat memperburuk gejala Lupus. Diduga oleh para dokter bahwa sinar matahari memiliki
banyak ekstrogen sehingga mempermudah terjadinya reaksi autoimmun. Tetapi bukan berarti bahwa penderita hanya bisa keluar pada malam hari. Pasien Lupus bisa saja keluar rumah sebelum pukul 09.00 atau sesudah pukul 16.00 WIB dan disarankan agar memakai krim pelindung dari sengatan matahari. Teriknya sinar matahari di negara tropis seperti Indonesia, merupakan faktor pencetus kekambuhan bagi para pasien yang peka terhadap sinar matahari dapat menimbulkan bercak-bercak kemerahan di bagian muka.kepekaan terhadap sinar matahari (photosensitivity) sebagai reaksi kulit yang tidak normal terhadap sinar matahari.
2.3 KLASIFIKASI Ada tiga jenis lupus, yaitu : 1. Lupus Eritematosus Sistemik (LES), dapat menimbulkan komplikasi seperti lupus otak, lupus paru-paru, lupus pembuluh darah jari-Jari tangan atau kaki, lupus kulit, lupus ginjal, lupus jantung, lupus darah, lupus otot, lupus retina, lupus sendi, dan lain-lain. 2. Lupus Diskoid, lupus kulit dengan manifestasi beberapa jenis kelainan kulit. Termasuk paling banyak menyerang. 3. Lupus Obat, yang timbul akibat efek samping obat dan akan sembuh sendiri dengan memberhentikan obat terkait. Umumnya berkaitan dengan pemakaian obat hydralazine (obat hipertensi) dan procainamide (untuk mengobati detak jantung yang tidak teratur).
2.4 PATOFISIOLOGI Penyakit SLE terjadi akibat terganggunya regulasi kekebalan yang menyebabkan peningkatan autoantibodi yang berlebihan. Gangguan imunoregulasi ini ditimbulkan oleh kombinasi antara faktor-faktor genetik, hormonal (sebagaimana terbukti oleh awitan penyakit yang biasanya terjadi selama usia reproduktif) dan lingkungan (cahaya matahari, luka bakar termal). Obat-obat tertentu seperti hidralazin, prokainamid, isoniazid, klorpromazin dan beberapa preparat antikonvulsan di samping makanan seperti kecambah alfalfa turut terlibat dalam penyakit SLE- akibat senyawa kimia atau obat-obatan. Pada SLE, peningkatan produksi autoantibodi diperkirakan terjadi akibat fungsi sel T-supresor yang abnormal sehingga timbul penumpukan kompleks imun dan kerusakan jaringan. Inflamasi akan menstimulasi antigen yang selanjutnya serangsang antibodi tambahan dan siklus tersebut berulang kembali. Uniknya, penyakit Lupus ini antibodi yang terbentuk dalam tubuh muncul berlebihan. Hasilnya, antibodi justru menyerang sel-sel jaringan organ tubuh yang sehat. Kelainan ini disebut autoimunitas. Antibodi yang berlebihan ini, bisa masuk ke seluruh jaringan dengan dua cara yaitu : Pertama, antibodi aneh ini bisa langsung menyerang jaringan sel tubuh, seperti pada sel-sel darah merah yang menyebabkan selnya akan hancur. Inilah yang mengakibatkan penderitanya kekurangan sel darah merah atau anemia. Kedua, antibodi bisa bergabung dengan antigen (zat perangsang pembentukan antibodi), membentuk ikatan yang disebut kompleks imun.Gabungan antibodi dan antigen mengalir bersama darah, sampai tersangkut di pembuluh darah kapiler akan menimbulkan peradangan. Dalam keadaan normal, kompleks ini akan dibatasi oleh sel-sel radang (fagosit). Tetapi, dalam keadaan abnormal, kompleks ini tidak dapat dibatasi dengan baik. Malah sel-sel radang tadi bertambah banyak sambil mengeluarkan enzim, yang menimbulkan peradangan di sekitar kompleks. Hasilnya, proses peradangan akan berkepanjangan dan akan merusak organ tubuh dan mengganggu fungsinya. Selanjutnya, hal ini akan terlihat sebagai gejala penyakit. Kalau hal ini terjadi, maka dalam jangka panjang fungsi organ tubuh akan terganggu
2.5 GEJALA KLINIS Gejala klinis dan perjalanan penyakit lupus sangat bervariasi. Penyakit dapat timbul mendadak disertai tandatanda terkenanya berbagai sistem dalam tubuh. Penyakit dapat juga menahun dengan gejala pada satu sistem yang lambat laun diikuti oleh terkenanya sistem yang lain. Pada tipe menahun terdapat masa bebas gejala dan masa kambuh kembali. Masa bebas gejala dapat berlangsung bertahun-tahun. Munculnya penyakit dapat spontan atau didahului faktor pemicu. Setiap serangan biasanya disertai gejala umum, seperti demam, badan lemah, nafsu makan berkurang dan berat badan menurun.
2.6 MANIFESTASI KLINIS a. Sistem Muskuloskeletal Artralgia, artritis (sinovitis), pembengkakan sendi, nyeri tekan dan rasa nyeri ketika bergerak, rasa kaku pada pagi hari. b. Sistem Integumen Lesi akut pada kulit yang terdiri atas ruam berbentuk kupu-kupu yang melintang pangkal hidung serta pipi.Ulkus oral dapat mengenai mukosa pipi atau palatum durum. c. Sistem Kardiak Perikarditis merupakan manifestasi kardiak. d. Sistem Pernafasan Pleuritis atau efusi pleura. e. Sistem Vaskuler
Inflamasi pada arteriole terminalis yang menimbulkan lesi papuler, eritematous dan purpura di ujung jari kaki, tangan, siku serta permukaan ekstensor lengan bawah atau sisi lateral tangan dan berlanjut nekrosis. f. Sistem Perkemihan Glomerulus renal yang biasanya terkena. g. Sistem Saraf Spektrum gangguan sistem saraf pusat sangat luas dan mencakup seluruh bentuk penyakit neurologik, sering terjadi depresi dan psikosis.
2.7 DIAGNOSIS Diagnosis SLE seringkali sulit ditegakkan karena gejala klinis penyakitnya sangat beraneka ragam. Untuk menegakkan diagnosis SLE umumnya harus dilakukan melalui dua tahapan. Pertama, menyingkirkan kemungkinan diagnosis penyakit lain. Kedua, mencari tanda dan gejala penyakit yang memiliki nilai diagnosis tinggi untuk SLE. Berdasarkan kriteria American College of Rheumatology (ACR) 1982, diagnosis lupus dapat ditegakkan secara pasti jika dijumpai 4 kriteria atau lebih dari 11 kriteria, yaitu: 1. Bercak-bercak merah pada hidung dan kedua pipi yang memberi gambaran seperti kupu-kupu (butterfly rash) 2. Kulit sangat sensitif terhadap sinar matahari (photohypersensitivity). 3. Luka di langit-langit mulut yang tidak nyeri. 4. Radang sendi ditandai adanya pembengkakan serta nyeri tekan sendi. 5. Kelainan paru. 6. Kelainan jantung. 7. Kelainan ginjal. 8. Kejang tanpa adanya pengaruh obat atau kelainan metabolik. 9. Kelainan darah (berkurangnya jumlah sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah). 10. Kelainan sistem kekebalan (sel LE positif atau titer anti-ds-DNA abnormal atau antibodi anti SM positif atau uji serologis positif palsu sifilis) 11. Antibodi antinuklear (ANA) positif. Kelainan yang paling sering adalah kelainan sendi dan kelainan kulit. Sendi yang sering terkena adalah sendi jarijari tangan, sendi lutut, sendi pergelangan tangan dan sendi pergelangan kaki. Kelainan kulit berupa butterfly rash dianggap khas dan banyak menolong dalam mengarahkan diagnosis lupus.
2.8 RESIKO PENYAKIT LUPUS TERHADAP KEHAMILAN Pada kehamilan dari perempuan yang menderita lupus, sering diduga berkaitan dengan kehamilan yang menyebabkan abortus, gangguan perkembangan janin atau pun bayi meninggal saat lahir. Tetapi hal yang berkebalikan juga mungkin atau bahkan memperburuk gejala lupus. Sering dijumpai gejala Lupus muncul sewaktu hamil atau setelah melahirkan. Dalam kehamilan sering terjadi kelainan kulit sehingga kambuhnya lupus dapat tidak diketahui, namun pada umumnya tetap dapat diobati dengan obat yang terseleksi. Lebih baik apabila ibu dengan lupus tidak mendapat obat-obatan selama hamil, namun belum ada laporan bahwa obat-obat untuk lupus (kecuali cyclophosphamide atau golongan kortikosteroid selain prednison) menyebabkan cacat janin meskipun jumlah kasus belum banyak. Risiko terhadap bayi: sekira 25% kehamilan pada ibu lupus akan berakhir dengan keguguran (pada ibu normal tanpa lupus keguguran sekira 8 10%), 25 50% dapat hamil cukup bulan, dan sekira 25 50% melahirkan pada usia kurang bulan. Sekira 3% bayi yang dilahirkan dapat mengalami neonatal lupus berupa kelainan pada kulit dan kelainan irama jantung. Tidak didapatkan peningkatan angka kejadian cacat fisik lainnya atau cacat
mental pada bayi yang dilahirkan oleh ibu dengan penyakit lupus. Demikian juga perkembangan bayi dengan nenonatal lupus pada umumnya normal. Risiko pada ibu meningkat dalam hal terjadinya preeklamsi/eklamsi (kenaikan tekanan darah yang terjadi dalam kehamilan, dapat disertai kejang), turunnya trombosit dan terdapatnya protein dalam air kemih.
2.9 PENATALAKSANAAN MEDIS a. Pengobatan Sampai sekarang, SLE memang belum dapat disembuhkan secara sempurna. Meskipun demikian, pengobatan yang tepat dapat menekan gejala klinis dan komplikasi yang mungkin terjadi. Program pengobatan yang tepat bersifat sangat individual tergantung gambaran klinis dan perjalanan penyakitnya. Pada umumnya, penderita SLE yang tidak mengancam nyawa dan tidak berhubungan dengan kerusakan organ vital dapat diterapi secara konservatif. Bila penyakit ini mengancam nyawa dan mengenai organ-organ vital, maka dipertimbangkan pemberian terapi agresif. Terapi konservatif maupun agresif sama-sama menggunakan terapi obat yang digunakan secara tunggal ataupun kombinasi. Terapi konservatif biasanya menggunakan anti-inflamasi non-steroid (indometasin, asetaminofen, ibuprofen), salisilat, kortikosteroid (prednison, prednisolon) dosis rendah, dan antimalaria (klorokuin). Terapi agresif menggunakan kortikosteroid dosis tinggi dan imunosupresif (azatioprin, siklofoshamid). Selain itu, penderita SLE perlu diingatkan untuk selalu menggunakan krem pelindung sinar matahari, baju lengan panjang, topi atau payung bila akan bekerja di bawah sinar matahari karena penderita sangat sensitif terhadap sinar matahari. Infeksi juga lebih mudah terjadi pada penderita SLE, sehingga penderita dianjurkan mendapat terapi pencegahan dengan antibiotika bila akan menjalani operasi gigi, saluran kencing, atau tindakan bedan lainnya. Salah satu bagian dari pengobatan SLE yang tidak boleh terlupakan adalah memberikan penjelasan kepada penderita mengenai penyakit yang dideritanya, sehingga penderita dapat bersikap positif terhadap terapi yang akan dijalaninya.
BAB III PEMBAHASAN
3.1 FREEKUENSI MASALAH KESEHATAN Frekuensi penyakit sistematic lupus erythematosus di dapat dari hasil survei dan dari data Rumah Sakit yang dikunjungi oleh pasien untuk mendapatkan pengobatan. Menurut data pustaka, di Amerika Serikat ditemukan 14,6 sampai 50,8 per 100.000 orang yang terkena penyakit lupus. Di Indonesia bisa dijumpai mencapai sekitar 50.000 penderita. Di RS Ciptomangunkusumo Jakarta, dari 71 kasus yang ditangani sejak awal 1991 sampai akhir 1996. Di Jawa Barat jumlah penderita lupus terdata mencapai 700 orang. Setiap bulan misalnya di RSHS selalu ada 10 pasien lupus baru. Saat ini, ada sekitar 5 juta pasien lupus di seluruh dunia dan setiap tahun ditemukan lebih dari 100.000 pasien baru, baik usia anak, dewasa, laki-laki, dan perempuan dan rasio penderita lupus di AS adalah 1:2.000 orang, China 1:1.000 orang, dan keturunan Afro-Karibia 1:500 orang.
3.2 PENYEBARAN MASALAH KESEHATAN a. Berdasarkan Variabel Manusia Umur dan Jenis kelamin
Secara epidemiologi, 90% penyakit lupus menyerang perempuan serta 10% anak-anak dan laki-laki Penyakit ini terutama diderita oleh wanita muda dengan puncak kejadian pada usia 15-50 tahun (selama masa reproduktif) dengan perbandingan wanita dan laki-laki 5:1. Penyakit ini sering ditemukan pada beberapa orang dalam satu keluarga. Ras Penyakit lupus atau systemic lupus erythematosus (SLE) lebih sering ditemukan pada ras tertentu seperti ras kulit hitam, Cina, dan Filipina. Bangsa Asia dan Afrika lebih rentan terkena penyakit in dibandingkan dengan kulit putih. Data di Amerika menunjukkan angka kejadian penyakit Lupus Ras Asia lebih tinggi dibandingkan ras Kaukasia.
Genetik Tidak diketahui gen atau gen gen apa yang menjadi penyebab penyakit tersebut, 10% dalam keluarga Lupus mempunyai keluarga dekat orang tua atau kaka adik) yang juga menderita lupus, 5% bayi yang dilahirkan dari penderita lupus terkena lupus juga, bila kembar identik, kemungkinan yang terkena Lupus hanya salah satu dari kembar tersebut. b. Berdasarkan Variabel Tempat Geografis Penyakit lupus atau systemic lupus erythematosus (SLE) lebih sering ditemukan pada daerah tropis, seperti di negara seperti Indonesia, merupakan faktor pencetus kekambuhan bagi para pasien yang peka terhadap sinar matahari. Terik sinar matahari dapat menimbulkan bercak-bercak kemerahan di bagian muka. c. Berdasarkan Variabel Waktu Penyakit lupus atau systemic lupus erythematosus (SLE) dapat timbul mendadak disertai tanda-tanda terkenanya berbagai sistem dalam tubuh. Penyakit dapat juga menahun dengan gejala pada satu sistem yang lambat laun diikuti oleh terkenanya sistem yang lain. Pada tipe menahun terdapat masa bebas gejala dan masa kambuh kembali. Masa bebas gejala dapat berlangsung bertahun-tahun. Munculnya penyakit dapat spontan atau didahului faktor pemicu.
3.3 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASALAH KESEHATAN Faktor penyebab terserangnya seseorang terhadap penyakit Lupus hingga kini belum diketahui, tetapi pengaruh lingkungan dan faktor genetik, hormon diduga sebagai penyebabnya, seperti infeksi, stress, makanan, antibiotik (khususnya kelompok sulfa dan penisilin), cahaya ultra violet (matahari) dan penggunaan obat obat tertentu. Faktor-faktor tersebut membuktukan bahwa terjadinya peningkatan jumlah penderita penyakit Lupus. Adanya gangguan imunoregulasi ini ditimbulkan oleh kombinasi antara faktor-faktor genetik, hormonal (sebagaimana terbukti oleh awitan penyakit yang biasanya terjadi selama usia reproduktif) dan lingkungan (cahaya matahari, luka bakar termal). Obat-obat tertentu seperti hidralazin, prokainamid, isoniazid, klorpromazin dan beberapa preparat antikonvulsan di samping makanan seperti kecambah alfalfa turut terlibat dalam penyakit SLE- akibat senyawa kimia atau obat-obatan.
2. Diagnosis Kriteria untuk klasifikasi SLE dari American Rheumatism Association (ARA, 1992). Seorang pasien diklasifikasikan menderita SLE apabila memenuhi minimal 4 dari 11 butir kriteria dibawah ini :
1. Artritis, arthritis nonerosif pada dua atau lebih sendi perifer disertai rasa nyeri, bengkak, atau efusi dimana tulang di sekitar persendian tidak mengalami kerusakan 2. Tes ANA diatas titer normal = Jumlah ANA yang abnormal ditemukan dengan immunofluoroscence atau pemeriksaan serupajika diketahui tidak ada pemberian obat yang dapat memicu ANA sebelumnya 3. Bercak Malar / Malar Rash (Butterfly rash) = Adanya eritema berbatas tegas, datar, atau berelevasi pada wilayah pipi sekitar hidung (wilayah malar) 4. Fotosensitif bercak reaksi sinar matahari = peka terhadap sinarUV/ matahari, menyebabkan pembentukan atau semakin memburuknya ruam kulit 5. Bercak diskoid = Ruam pada kulit 6. Salah satu Kelainan darah; - Anemia hemolitik, - Leukosit < 4000/mm, - Limfosit