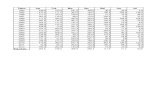LAPORAN PRAKTIKUM HIDROLOGI
-
Upload
ahyat-hartono -
Category
Documents
-
view
588 -
download
7
Transcript of LAPORAN PRAKTIKUM HIDROLOGI

1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam meteorologi, presipitasi (juga dikenal sebagai satu kelas dalam
hidrometeor, yang merupakan fenomena atmosferik) adalah setiap produk dari
kondensasi uap air di atmosfer. Ia terjadi ketika atmosfer (yang merupakan suatu
larutan gas raksasa) menjadi jenuh dan air kemudian terkondensasi dan keluar dari
larutan tersebut (terpresipitasi). Udara menjadi jenuh melalui dua proses,
pendinginan atau penambahan uap air.
Presipitasi yang mencapai permukaan bumi dapat menjadi beberapa
bentuk, termasuk diantaranya hujan, hujan beku, hujan rintik, salju, sleet, and
hujan es. Virga adalah presipitasi yang pada mulanya jatuh ke bumi tetapi
menguap sebelum mencapai permukaannya.
Dalam menganalis data hujan suatu wilayah diperlukan 3 metode, yaitu
metode rata-rata hitung, metode thiessen, dan metode isohyet.
1.2 Tujuan
Tujuan dari praktikum analisis curah hujan ini antara lain adalah untuk
mengetahui cara menghitung curah hujan rata-rata daerah aliran (areal rainfall).

2
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Presipitasi
Presipitasi adalah salah satu komponen utama dalam siklus air, dan
merupakan sumber utama air tawar di planet ini.Diperkirakan sekitar 505,000 km³
air jatuh sebagai presipitasi setiap tahunnya, 398,000 km³ diantaranya jatuh di
lautan.[2] Bila didasarkan pada luasan permukaan Bumi, presipitasi tahunan global
adalah sekitar 1 m, dan presipitasi tahunan rata-rata di atas lautan sekitar 1.1 m.
Presipitasi perlu diukur untuk mendapatkan data hujan yang sangat berguna bagi
pernecanaan hidrologis, semisal perencanaan pembangunan bendung, dam, dan
sebagainya. Salah satu alat ukurnya yang sederhana adalah sebagai berikut. yang
ini merupakan alat ukur hujan harian.
Pengukurannya dengan mendukur kedalaman air yang terkumpul dalam botol
pengumpul di baigan tengah tersebut.
Penempatan alat ukur hujan harus di tempat terbuka, harus dilindungi dari
gangguan binatang dan manusia, selalu dijaga agar tetap bersih, data hujan yang
terkumpul tiap harinya harus diukur dengan teratur pada jam yang sama tiap
harinya (ini menyebabkan Indonesia sangat kekurangan data hujan, karena jarang
ada orang yang mau secara rutin mengecek alat ukur hujan). Jarak minimal alat
ukur hujan terhadap bangunan yang terdekat dengannya adalah sejauh empat kali
tinggi bangunan terdekat tersebut.
Presipitasi merupakan peristiwa jatuhnya cairan (dapat berbentuk cair atau beku)
dari atmosphere ke permukaan bumi.
a. Presipitasi cair dapat berupa hujan dan embun
b. Presipitasi beku dapat berupa salju dan hujan es.
— Semua bentuk hasil kondensasi uap air yang terkandung di atmosfer.
— Kondensasi
Ketika uap air mengembang, mendingin dan kemudian berkondensasi, biasanya
pada partikel-partikel debu kecil di udara. Ketika kondensasi terjadi uap air dapat
berubah menjadi cair kembali atau langsung berubah menjadi padat (es, salju,

3
hujan batu (hail)). Partikel-partikel air ini kemudian berkumpul dan membentuk
awan.
Proses terjadinya :
Penguapan air dari tubuh air permukaan maupun vegetasi akibat sinar matahari
atau suhu yang tinggi.
Pergerakan uap air di atmosfer akibat perbedaan tekanan uap air.
Uap air bergerak dari tekanan uap air besar ke kecil.
Pada ketinggian tertentu uap air akan mengalami penjenuhan, jika diikuti dengan
kondensasi maka uap air akan berubah menjadi butiran-butiran hujan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya presipitasi diantara lain
berupa :
a) Adanya uap air di atmosphere
b) Faktor-faktor meteorologis
c) Lokasi daerah
d) Adanya rintangan misal adanya gunung.
Udara di atmosfer akan mengalami proses pendinginan melalui beberapa
cara umumnya adalah akibat pertemuan antara dua massa udara dengan suhu yang
berbeda atau oleh sentuhan udara dengan obyek dingin. Awan merupakan indikasi
awal terjadinya presipitasi tetapi awan tidak otomatis menandakan akan adanya
hujan.
Mekanisme berlangsungnya hujan melibatkan tiga faktor utama :
1. Kenaikan massa uap air ke tempat yang lebih tinggi sampai saatnya atmosfer
menjadi jenuh.
2. Terjadinya kondensasi atas partikel-partikel uap air di atmosfer.
3. Partikel uap air tersebut bertambah besar sejalan dengan waktu, selanjutnya
jatuh ke bumi dan permukaan laut (sebagai hujan) karena faktor gravitasi.
2.2 Curah Hujan Rata-rata DAS
Beberapa cara perhitungan untuk mencari curah hujan rata-rata daerah
aliran, yaitu :
Arithmatic Mean Method

4
perhitungan curah hujan rata-rata digunakan metode rata-rata aljabar karena
dengan cara ini data yang diperoleh lebih obyektif jika dibandingkan dengan cara
isohyet, di mana faktor subyektif ikut menentukan.
Metode Theissen akan memberikan hasil yang lebih teliti daripada cara
aljabar tetapi untuk penentuan titik pengamatannya dan pemilihan ketinggian akan
mempengaruhi ketelitian yang akan didapat juga seandainya untuk penentuan
kembali jaringan segitiga jika terdapat kekurangan pengamatan pada salah satu
titik pengamatan (Sosrodarsono, Suyono, 1987:27). ⋯……….
di mana : R = curah hujan daerah (mm)
N = jumlah titik-titik (pos) pengamatan
R1, R
2,...R
n = curah hujan ditiap titik pengamatan (mm)
Thiessen Method
Cara ini dengan memperhitungkan luas daerah yang diwakili oleh stasiun
yang bersangkutan (luas daerah pengaruh), untuk dgunakan sebagai faktor dalam
menghitung hujan rata-rata.
Menurut Thiessen luas daerah pengaruh dari setiap stasiun dengan cara
Menghubungkan stasiun-stasiun dengan suatu garis sehingga membentuk poligon-
poligon segitiga.
Menarik sumbu-sumbu dari poligon-poligon segitiga.
Perpotongan sumbu-sumbu ini akan membentuk luasan daerah pengaruh
dari tiap-tiap stasiun. Luas daerah pengaruh masing-masing stasiun dibagi dengan
luas daerah aliran disebut sebagai Koefisien Thiessen masing-masing stasiun
(weighting factor).
Hujan rata-rata di daerah aliran dirumuskan sebagai berikut: ⋯……………⋯…..
Dimana :
A = Luas daerah aliran (km2)
An = Luas daerah pengaruh stasiun n (km2)

5
Wn = Faktor pembobot daerah pengaruh stasiun n
Rn = Tinggi hujan pada stasiun n (mm)
Metode Thiessen sesuai untuk daerah dengan jarak penakar hujan yang tidak
merata.
Ishohyet Method
Isohyet adalah garis yang menunjukkan tempat-tempat yang mempunyai
tinggi hujan yang sama.
Cara ini adalah cara yang paling teliti, tetapi cukup sulit pembuatannya.
Pada umumnya digunakan untuk hujan tahunan, karena terlalu banyak variasinya,
sehingga isohyet akan berubah-ubah.
2.3 Curah Hujan Efektif
Curah hujan efektif adalah curah hujan yang jatuh selama masa tumbuh
tanaman, yang dapat digunakan untuk memenuhi air konsumtif tanaman.
Besarnya curah hujan ditentukan dengan 70% dari curah hujan rata – rata tengah
bulanan dengan kemungkinan kegagalan 20% ( Curah hujan R80 ).
Dengan
menggunakan Basic Year dengan rumus :
R80
= n/5 + 1
dengan n adalah periode lama pengamatan.
Curah hujan efektif diperoleh dari 70% x R80
per periode waktu pengamatan.
Apabila data hujan yang digunakan 10 harian maka persamaannya menjadi :
Repadi
=(R80
x 70%)/10 mm/hari.
Retebu
=(R80
x60%)/ 10 mm/hari.
Repolowijo
= (R80
x 50%) / 10 mm/hari
Curah hujan efektif juga dapat dihitung dengan menggunakan metode Log
Pearson III berdasarkan data hujan yang tersedia.

6
2.4 Debit Andalan
Debit andalan merupakan debit minimum sungai untuk kemungkinan
untuk kemungkinan terpenuhi yang sudah ditentukan yang dapaat dipakai untuk
irigasi. Misalnya ditetapkan debit andalan 80% berarti akan dihadapi resiko
adanya debit-debit yang lebih kecil dari debit andalan sebesar 20% pengamatan.
Debit minimum sungai dianalisis atas dasar data debit harian sungai. Agar
analisisnya cukup tepat dan andal, catatan data yang diperlukan harus meliputi
jangka waktu paling sedikit 20 tahun. Jika persyaratan ini tidak bisa dipenuhi,
maka metode hidrologi analitis dan empiris bisa dipakai. Dalam menghitung debit
andalan, kita harus mempertimbangkan air yang diperlukan dari sungai di hilir
pengambilan (SPI KP-01 :1986).
Dari data debit inflow yang diperoleh pada studi ini, maka diketahui pengisian
bendungan berlangsung tiap bulannya selama setahun. Data ini nantinya akan
dipakai dalam perhitungan debit yang masuk ke waduk.

7
BAB III
METODOLOGI
3.1 Alat dan Bahan
Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah kalkulator dan
alat tulis digunakan untuk menghitung dan mencatat hasil perhitungan. Bahan
yang digunakan dalam praktikum ini adalah data curah hujan didaerah aliran
sungan Citanduy.
3.2 Metode Pelaksanaan
Langkah-langkah praktikum yang dilakukan antara lain :
1) Menyediakan kalkulator dan alat tulis;
2) Menghitung rata-rata curah hujan bulanan disetiap pos;
3) Mencatat hasilnya pada kolom yang telah disediakan;
4) Menghitung curah hujan rata-rata didaerah aliran sungan Citanduy;
5) Mencatat hasilnya pada kolom yang disediakan;
6) Menghitung curah hujan tahunan menggunakan 3 metode.
7) Mencatat hasilnya pada kolom yang disediakan.

8
BAB IV
HASIL PRAKTIKUM
4.1 Data Pos Curah Hujan Pagerageng
Tahun Curah Hujan (mm) Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
1989 363 716 531 159 204 379 193 55 15 212 363 344 1990 342 510 305 233 259 0 0 31 297 162 206 549 1991 773 486 255 382 259 20 20 5 5 38 462 288 1992 471 461 328 255 189 57 49 91 214 395 367 575 1993 508 411 421 437 142 110 7 185 49 62 247 422 1994 834 555 572 216 89 9 0 2 1 63 237 194 1995 360 693 636 481 201 269 43 8 69 290 574 435 1996 332 732 300 78 222 0 67 242 41 384 310 226 1997 476 207 85 325 118 0 3 1 0 11 6 253 1998 105 236 329 153 260 63 151 98 120 210 459 314 1999 105 236 329 153 260 63 84 98 120 210 459 314 2000 228 347 260 108 112 38 55 22 35 195 330 201 2001 303 113 314 305 95 116 64 9 80 257 812 236 2002 392 85 98 59 123 79 73 5 9 9 260 355 2003 529 302 176 159 132 22 12 0 26 175 329 196 2004 532 228 541 274 215 62 54 7 123 135 188 443 2005 385 332 420 242 78 285 193 121 113 215 508 687 2006 433 219 142 412 449 43 24 12 1 5 178 314
Rata-rata 415 382 336 246 189 90 61 55 73 168 350 353
4.2 Data Pos Curah Hujan Rajadesa
Tahun Curah Hujan (mm) Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des
1989 349 687 510 152 195 364 185 52 14 204 348 330 1990 328 490 292 228 249 0 0 29 285 156 198 527 1991 742 467 245 367 249 19 19 5 5 36 443 276 1992 452 443 314 244 181 54 47 87 205 379 352 552 1993 487 395 404 419 136 106 6 178 47 60 237 405 1994 801 532 549 207 85 9 0 0 0 60 228 186 1995 345 665 610 461 192 258 41 7 66 278 551 418 1996 318 703 288 75 213 0 64 232 39 369 298 217 1997 457 199 81 312 113 0 3 0 0 11 6 242 1998 101 226 316 147 250 61 145 94 115 202 441 301 1999 101 226 316 147 250 61 81 94 115 202 441 301

9
2000 218 334 250 104 107 36 53 21 34 187 317 193 2001 291 108 301 293 91 111 61 9 77 246 780 227 2002 376 82 94 57 118 75 70 5 9 9 250 341 2003 508 290 169 153 127 21 12 0 24 168 316 188 2004 511 219 519 263 206 60 51 7 118 129 181 425 2005 370 319 404 232 75 274 186 116 108 207 488 659 2006 415 210 136 396 431 41 23 12 1 5 171 301
Rata-rata 398 366 322 237 182 86 58 53 70 162 336 338
4.3 Data Pos Curah Hujan Manonjaya
Tahun Curah Hujan (mm) Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des
1989 320 630 467 139 179 334 169 48 13 187 319 302 1990 301 449 268 209 228 0 0 27 261 143 181 483 1991 680 428 225 337 228 18 17 4 5 33 406 253 1992 414 406 288 224 166 50 43 80 188 347 323 506 1993 447 362 370 384 125 97 6 163 43 55 217 371 1994 734 488 503 190 78 8 0 1 0 55 209 170 1995 316 610 559 423 176 237 37 7 61 255 505 383 1996 292 644 264 69 195 0 59 213 36 338 273 199 1997 419 182 74 286 104 0 3 0 0 10 5 222 1998 92 207 289 135 229 56 133 86 106 185 404 276 1999 92 207 289 135 229 56 74 86 106 185 404 276 2000 200 306 229 95 98 33 48 99 31 172 290 177 2001 267 99 276 268 84 102 56 8 70 226 715 208 2002 345 75 86 52 108 69 64 5 8 8 229 312 2003 466 265 155 140 116 19 11 0 22 154 289 173 2004 468 200 476 241 189 55 47 6 108 118 166 390 2005 339 293 370 213 69 251 170 107 99 190 447 604 2006 381 193 125 363 395 38 21 11 1 4 157 276
Rata-rata 365 336 295 217 166 79 53 53 64 148 308 310
4.4 Data Pos Curah Hujan Ciputrahaji
Tahun Curah Hujan (mm) Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des
1989 305 601 446 133 171 318 162 46 13 178 305 289 1990 287 428 256 199 218 0 0 26 249 136 173 461 1991 649 408 215 321 218 17 16 4 4 32 388 242 1992 395 387 275 214 158 47 41 76 179 331 308 483 1993 426 345 353 367 119 92 5 155 41 52 207 354

10
1994 701 466 480 181 74 8 0 1 0 53 199 163 1995 302 582 534 404 168 226 36 6 58 243 482 365 1996 278 615 252 66 186 0 56 203 34 323 260 190 1997 400 174 71 273 99 0 3 0 0 10 5 212 1998 88 198 276 129 218 53 127 82 101 176 386 263 1999 88 198 276 129 218 53 71 82 101 176 386 263 2000 191 292 218 91 94 32 46 18 29 164 277 169 2001 255 95 264 256 80 97 54 8 67 215 682 198 2002 329 71 82 50 103 66 62 5 8 8 218 298 2003 445 253 148 134 111 18 10 0 21 147 276 165 2004 447 191 454 230 180 52 45 6 103 113 158 372 2005 324 279 353 203 66 239 163 102 95 181 427 577 2006 363 184 119 346 377 36 20 10 1 4 150 264
Rata-rata 349 320 282 207 159 75 51 46 61 141 294 296
4.5 Data Besar Curah Hujan (Ri) Pertahun Masing-masing Daerah
Daerah Ri
Pagerageng
Rajadesa
Manonjaya
Ciputrahaji
2717
2608
2395
2281
4.6 Perhitungan
a) Luas Area dengan menggunakan metode Thiessen
A1(Pageregang)= 19,3x 5,625x 1011 cm3= 108,5625x1013 mm2
A2(Rajadesa)= 29,5x 5,625x1011 cm3= 165,9375x1013 mm2
A3(Manonjaya)=13x 5,625x1011cm3 = 73,125x1013 mm2
A4(Ciputrahaji)= 16,5x5,625x1011cm3= 92,8125x1013 mm2
b) Luas Area deang menggunakan metode Isohiyet
A1(Pageregang)= 8,5x 5,625x 1011 cm3= 47,8125x1013 mm2
A2(Rajadesa)= 30,5x 5,625x1011 cm3= 171,5625x1013 mm2
A3(Manonjaya)= 16x 5,625x1011cm3 = 90x1013 mm2
A4(Ciputrahaji)= 15,5x5,625x1011cm3= 87,1875x1013 mm2

11
c) Curah Hujan Rata-rata Tahunan DAS Citanduy (Metode Thiessen)
푅 = 퐴1.푅1 + 퐴2.푅2 + 퐴3.푅3 + 퐴4.푅4
퐴1 + 퐴2 + 퐴3 + 퐴4
푅 = (108,5625.2717 + 165,9375.2608 + 73,125.2395 + 92,8125.2281)푥10
(108,5625 + 165,9375 + 73,125 + 92,8125)푥10
푅 = 2635,95913
푅 = 2636 푚푚/푡ℎ
d) Curah Hujan Rata-rata Tahunan DAS Citanduy (Metode Thiessen)
푅 = 퐴1.푅1 + 퐴2.푅2 + 퐴3.푅3 + 퐴4.푅4
퐴1 + 퐴2 + 퐴3 + 퐴4
푅 = (47,8125.2250 + 171,5625.2350 + 90.2550 + 87,1875.2750)푥10
(47,8125 + 171,5625 + 90 + 87,1875)푥10
푅 = 2471,276596
푅 = 2471 푚푚/푡ℎ

12
BAB V
PEMBAHASAN
Praktikum kali ini menghitung daerah rata-rata daerah aliran(Areal
Rainfall) yaitu daerah aliran sungai Citanduy, dengan menggunakan 3 metode
perhitungan, yaitu metode rata-rata hitung, metode thiessen dan metode isohyet.
Pengukuran Curah Hujan rata-rata daerah aliran
Pengukuran curah hujan dilakukan dengan menggunakan peta yang telah
disediakan, menggunakan ketiga metode tersebut. Dalam perhitungan
menggunakan metode rata-rata hitung(rithmatic Mean), yaitu dengan cara mencari
rata-rata hujan didalam suatu daerah aliran yang terdapat pada tabel dari semua
stasiun dan membaginya dengan jumlah stasiun tersebut. Menggunakan metode
thiessen yang ditentukan dengan cara membuat poligon pada peta antara pos
hujan pada wilayah DAS,kemudian tinggi hujan rata-rata daerah aliran dihitung
dari jumlah perkalian antara tiap-tiap luas poligon dan tinggi hujannya dibagi
dengan seluruh DAS. Metode isohyet ditentukan dengan cara menggunakan peta
garis konturkedalaman hujan suatu daerah dan kedlaman hujan rata-rata DAS
dihitung dari jumlah perkalian kedalaman hujan rata-rata antara garis isohyet
dengan luas antara kedua garis isohyet tersebut,dibagi luas DAS.
Ada beberapa kesulitan yang terjadi dalam menghitung luasan daerah, karena
menghitung tiap mm pada mm blok yang terdapat gambar peta, ketelitian sangat
mempengaruhi perhitungan data.
Pada perhitungan dilakukan tiga metode yaitu metode rata-rata hitung, metode
Thiessen, dan metode isohiyet. Pada metode rata-rata hitung, dilakukan dengan
mencari rata-rata data curah hujan setiap bulan di setiap pos curah hujan
kemudian dijumlahkan sebagai rata-rata curah hujan tahunan.
Pada metode thiessen, curah hujan tahunan dihitung dengan menjumlahkan
perkalian antara luas daerah pos curah hujan dengan rata-rata curah hujan tahunan
di pos tersebut dibagi dengan jumlah luas area total daerah aliran sungai Citanduy.
Untuk metode isohiyet, curah hujan tahunan dihitung dengan menjumlahkan
perkalian antara luas pos curah hujan dengan rata-rata batas kontur pada peta
dibagi dengan jumlah total area pada daerah aliran sungai Citanduy.

13
BAB VI
KESIMPULAN
Kesimpulan dari praktikum mengenai perhitungan curah hujan rata-rata
daerah aliran sungai Citanduy ini adalah sebagai berikut.
1) Cara menghitung curah hujan rata-rata daerah aliran sungai citanduy, dapat
dilakukan dengan tiga metode yaitu rata-rata hitung, thiessen, dan isohiyet;
dan
2) Dari hasil perhitungan, diperoleh curah hujan rata-rata daerah aliran sungai
Citanduy berkisar anatara 2400-2600 mm/tahun.

14
DAFTAR PUSTAKA
Asdak, Chay. 2007. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Gadjah
Mada University Press: Yogyakarta.
Dwiratna NP., Sophia. 2011. Penuntun Praktikum Hidrologi. Jurusan Teknik dan
Manajemen Industri Pertanian FTIP Unpad: Jatinangor.
Winnie. 2009. Hidrologi. http://www.cwien.wordpress.com/2009/05/31/hidrologi/
diakses pada 26 September 2011 pukul 12.24 WIB.
Suroso. 2006. Jurnal Teknik Sipil Analisi Curah Hujan untuk Membuat Kurva
Intensity-Duration-Frequency (IDF) di Kawasan Rawan Banjir
Kabupaten Banyumas. Universitas Jendral Soedirman: Purwokerto.