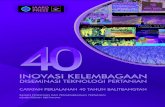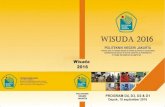Isi
-
Upload
yudhikaiway -
Category
Documents
-
view
47 -
download
0
Transcript of Isi

BAB I
Pendahuluan
1.1 Latar belakang
Kehamilan adalah suatu masa yang dinanti oleh setiap pasangan suami
istri yang dimulai dari terjadinya pembuahan (konsepsi) sampai lahirnya anak. Sel
telur yang sudah dibuahi akan menempel pada dindin rahim dan kemudian
tumbuh dan berkembang sampai mencapai 40 minggu atau 9 bulan. Kehamilan 40
minggu ini disebut kehamilan matur (cukup bulan). (Ibrahim, 1993 dalam
Pasaribu, 2005).
WHO memperkirakan bahwa sekitar 15% dari seluruh wanita yang hamil
akan berkembang menjadi komplikasi yang berkaitan dengan kehamilannya serta
dapat mengancam jiwaya. Dari 5.600.000 wanita hamil di Indonesia, sebagian
besar akan mengalami suatu komplikasi atau masalah yang bisa menjadi fakta.
Di Indonesia, Program kesehatan Ibu dan Anak (KIA) merupakan salah
satu prioritas Kementerian Kesehatan dan keberhasilan program KIA menjadi
salah satu indikator utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) 2005 – 2025. Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia
membuat pemerintah menempatkan upaya penurunan AKI sebagai program
prioritas dalam pembangunan kesehatan. Menurut Survei Demografi Kesehatan
Indonesia Angka Kematian Ibu saat ini telah menunjukkan terjadinya penurunan
dari 307/100.00 Kelahiran Hidup, ditahun 2002 menjadi 228/100.00 Kelahiran
Hidup ditahun 2007 dan 226/100.00 Kelahiran Hidup ditahun 2009. Namun
program percepatan penurunan AKI diupayakan terus untuk mencapai target
Pembangunan Milenium (MDG) 102/100.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2015.
Berdasarkan data informasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua pada tahun
2008 Angka Kematian Ibu di Papua masih tinggi jika dibandingkan dengan
provinsi lain. Di Papua, terutama di daerah pedalaman, kematian ibu melahirkan,
bayi, dan anak balita, menjadi ancaman serius. AKI di Papua 362 per 100.000

kelahiran hidup, di atas angka nasional 228 per 100.000 kelahiran hidup. Angka
kematian bayi di Papua pun tertinggi di Indonesia, 41 per 1.000 kelahiran hidup,
jauh lebih tinggi daripada angka nasional 34 per 1.000 kelahiran hidup.
Setiap tahun diperkirakan terjadi 20.000 kematian ibu karena komplikasi
melahirkan dan selama kehamilan. Penyebab utama kematian ibu di Papua adalah
perdarahan, eklampsia yang menyebabkan tekanan darah tinggi sewaktu
kehamilan, komplikasi aborsi, infeksi dan lama partus. Sejumlah komplikasi
sewaktu melahirkan dapat dicegah, misalnya komplikasi akibat aborsi yang tidak
aman. Komplikasi menyumbang 6% dari angka kematian.
Sangat sulit diketahui sebelumnya bahwa kehamilan akan menjadi
masalah atau tidak, dan sistem penilaian risiko tidak dapat memprediksi apakah
ibu hamil akan bermasalah atau tidak selama kehamilannya. Oleh karena itu
asuhan pemeriksaan kehamilan/antenatal care (ANC) yang dilakukan secara
teratur dan rutin merupakan cara yang paling tepat dan penting untuk memonitor
dan mendukung kesehatan ibu hamil normal dan mendeteksi ibu dengan
kehamilan normal. Ibu hamil sebaiknya mengunjungi bidan atau dokter sedini
mungkin di tempat pelayanan kesehatan seperti Puskesmas, semenjak ia merasa
dirinya hamil untuk mendapatkan pelayanan/asuhan antenatal care (Saifuddin,
2002).
1.2 Perumusan masalah

Bagaimana gambaran kepatuhan ibu hamil terhadap kunjungan
pemeriksaan kehamilan (antenatal care) ANC di Puskesmas Sentani
periode Juni 2012 - Juni 2013?
1.3 Tujuan penelitian :
1. Tujuan umum :
Mengetahui gambaran kepatuhan ibu hamil terhadap kunjungan
pemeriksaan kehamilan (antenatal care) ANC.
2. Tujuan khusus :
1. Mengetahui gambaran kepatuhan ibu hamil terhadap kunjungan
pemeriksaan kehamilan (antenatal care) ANC berdasarkan
umur.
2. Mengetahui gambaran kepatuhan ibu hamil terhadap kunjungan
pemeriksaan kehamilan (antenatal care) ANC berdasarkan
pendidikan.
3. Mengetahui gambaran kepatuhan ibu hamil terhadap kunjungan
pemeriksaan kehamilan (antenatal care) ANC berdasarkan
paritas.
1.4 Manfaat penelitian :
1. Bagi Puskesmas Sentani.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan
dalam meningkatkan pemeriksaan dan pelayanan ANC.
2. Bagi masyarakat sentani dan sekitarnya
Hasil penilitian ini diharapkan sebagai informasi mengenai
pentingnya kunjungan ibu hamil terhadap pemeriksaan ANC.
3. Bagi institusi Fakultas Kedokteran Universitas
Cenderawasih

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk
memperluas wawasan dan menambah kepustakaan mahasiswa
4. Bagi peneliti
Untuk menambah kemampuan peneliti dalam meneliti dan
menyusun suatu skripi ilmiah yang sitematis.
5. Bagi Peneliti Selanjutnya
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
sebagai informasi, perbandingan, serta referensi bagi peneliti
selanjutnya.
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
A. Kehamilan
1. Pengertian Kehamilan
Kehamilan adalah kondisi dimana seorang wanita memiliki janin yang
sedang tumbuh di dalam tubuhnya (yang pada umumnya di dalam rahim).
Kehamilan pada manusia berkisar 40 minggu atau 9 bulan, dihitung dari awal
periode menstruasi terakhir sampai melahirkan. Kehamilan merupakan suatu
proses reproduksi yang perlu perawatan khusus, agar dapat berlangsung dengan
baik kehamilan mengandung kehidupan ibu maupun janin. Resiko kehamilan ini
bersifat dinamis, karena ibu hamil yang pada mulanya normal, secara tiba-tiba
dapat menjadi berisiko tinggi. Faktor resiko pada ibu hamil seperti umur terlalu
muda atau tua, banyak anak, dan beberapa faktor biologis lainnya adalah keadaan
yang secara tidak langsung menambah resiko kesakitan dan kematian pada ibu
hamil. Resiko tinggi adalah keadaan yang berbahaya dan mungkin terjadi
penyebab langsung kematian ibu, misalnya pendarahan melalui jalan lahir,
eklamsia, dan infeksi. Beberapa faktor resiko yang sekaligus terdapat pada
seorang ibu dapat menjadikan kehamilan berisiko tinggi.
2. Tanda dan Gejala Awal Kehamilan
Tanda dan gejala pada masing-masing wanita hamil berbeda-beda. Ada
yang mengalami gejala-gejala kehamilan sejak awal, ada yang beberapa minggu
kemudian, atau bahkan tidak memiliki gejala kehamilan dini. Namun, tanda yang
pasti dari kehamilan adalah terlambatnya periode menstruasi. Selain itu
didapatkan tanda-tanda lain yaitu :
1) Nyeri atau payudara yang terasa membesar, keras, sensitif dengan
sentuhan. Tanda ini muncul dalam waktu 1-2 minggu setelah konsepsi
(pembuahan). Dalam waktu 2 minggu setelah konsepsi, payudara
seorang wanita hamil akan mengalami perubahan untuk persiapan
produksi ASI yang dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron.

2) Mual pagi hari (morning sickness) umum terjadi pada triwulan
pertama. Meskipun disebut morning sickness, namun mual dan muntah
dapat terjadi kapan saja selama kehamilan. Penyebab mual dan muntah
ini adalah perubahan hormonal yang dapat memicu bagian dari otak
yang mengontrol mual dan muntah. Gejala ini dialami oleh 75%
wanita hamil.
3) Mudah lelah, lemas, pusing, dan pingsan adalah gejala kehamilan yang
disebabkan oleh pelebaran pembuluh darah dalam kehamilan atau
kadar gula darah yang rendah.
4) Sakit kepala pada umumnya muncul pada minggu ke-6 kehamilan
yang disebabkan oleh peningkatan hormon.
5) Konstipasi (sulit BAB) terjadi karena peningkatan hormon progesteron
yang menyebabkan kontraksi usus menjadi lebih pelan dan makanan
lebih lambat melalui saluran pencernaan.
6) Perubahan mood karena pengaruh hormon.
7) Bercak perdarahan. Terjadi ketika telur yang sudah dibuahi
berimplantasi (melekat) ke dinding rahim sekitar 10-14 hari setelah
fertilisasi (pembuahan). Tipe perdarahan umumnya sedikit, bercak
bulat, berwarna lebih cerah dari darah haid, dan tidak berlangsung
lama.
3. Suplemen yang dianjurkan selama kehamilan
1) Asam folat. Asam folat yang dikonsumsi sebelum hamil dan selama
kehamilan melindungi dari gangguan saraf pada janin (anensefali,
spina bifida). Wanita hamil disarankan mengkonsumsi asam folat 400
μg/hari selama 12 minggu kehamilan karena kebutuhan asam folat
tidak dapat dipenuhi hanya dari makanan.
2) Zat besi. Zat besi adalah komponen utama dari hemoglobin yang
bekerja mengangkut oksigen di dalam darah. Selama kehamilan,
suplai darah meningkat untuk memberikan nutrisi ke janin. Suplemen
besi yang dibutuhkan adalah 30 – 50 mg/hari dan disarankan pada

wanita hamil dengan hemoglobin < 10 atau 10,5 g/dl pada akhir
kehamilan. Selain suplemen, zat besi juga terkandung pada daging,
telur, kacang, sayuran hijau, gandum, dan buah-buahan kering.
Suplemen besi sebaiknya dikonsumsi diantara waktu makan dengan
perut yang kosong atau diikuti jus jeruk untuk meningkatkan
penyerapan.
3) Kalsium. Kalsium penting di dalam mengatur kekuatan tulang wanita
hamil dan pertumbuhan tulang bagi janin. Kalsium yang disarankan
sebanyak 1.200 mg untuk memenuhi kebutuhan ibu dan janin.
Kalsium sebaiknya dikonsumsi ketika sedang makan, diikuti dengan
jus buah yang kaya vitamin C untuk meningkatkan penyerapan.
B. ANC (antenatal care)
1. Pengertian Pemeriksaan Antenatal Care
Pemeriksaan Antenatal Care (ANC) adalah pemeriksaan kehamilan untuk
mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil, hingga mampu
menghadapi persalinan, kala nifas, persiapan pemberiaan ASI dan kembalinya
kesehatan reproduksi secara wajar (Manuaba, 2008).
2. Tujuan ANC (Antenatal Care)
a. Tujuan Umum
1. Memantau kemajuan kehamilan untuk memastikan kesehatan
ibu dan tumbuh kembang janin.
2. Meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, maternal
dan sosial ibu dan bayi.
3. Mengenal secara dini adanya komplikasi yang mungkin terjadi
selama hamil, termasuk riwayat penyakit secara umum,
kebidanan dan pembedahan.

4. Mempersiapkan persalinan cukup bulan, melahirkan dengan
selamat ibu maupun bayinya dengan trauma seminimal
mungkin.
5. Mempersiapkan ibu agar masa nifas berjalan normal dan
pemberian ASI Eksklusif.
6. Mempersiapkan peran ibu dan keluarga dalam menerima
kelahiran bayi agar dapat tumbuh kembang secara normal.
7. Menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan perinatal.
b. Tujuan Khusus
1. Mengenali dan mengobati penyulit-penyulit yang mungkin
diderita sedini mungkin.
2. Menurunkan angka morbilitas ibu dan anak.
3. Memberikan nasihat-nasihat tentang cara hidup sehari-hari dan
keluarga berencana, kehamilan, persalinan, nifas dan laktasi.
3. Manfaat Antenatal Care (ANC)
Antenatal Care (ANC) memberi manfaat dengan ditemukannya kelainan
yang menyertai kehamilan secara dini, sehingga dapat diperhitungkan dan
dipersiapkan langkah-langkah dalam pertolongan persalinannya.
Sehingga kesehatan ibu yang optimal dapat meningkatkan kesehatan,
pertumbuhan dan perkembangan janin. Selain itu, pemeriksaan kehamilan
(Antenatal Care) yang diberikan kepada ibu hamil secara berkala dan teratur
merupakan upaya bersama antara petugas kesehatan dan ibu hamil, suami,
keluarga dan masyarakat, mengenai :
1) Aspek kesehatan dari ibu dan janin untuk menjaga kelangsungan
kehamilan, pertumbuhan janin dalam kandungan, kelangsungan
hidup ibu dan bayi setelah lahir.
2) Aspek psikologi, agar dalam menghadapi kehamilan dan
persalinannya ibu hamil mendapatkan rasa aman, tenang, terjamin
dan terlindungi keselamatan diri dan bayinya.

3) Aspek sosial ekonomi, ibu hamil dari keluarga miskin (gakin) pada
umumnya tergolong dalam kelompok gizi kurang, anemia,
penyakit menahun. Ibu resiko tinggi atau ibu dengan komplikasi
persalinan dari keluarga miskin membutuhkan dukungan biaya dan
transportasi untuk rujukan ke rumah sakit.
4. Jadwal Pemeriksaan Antenatal care (ANC)
Kunjungan ibu hamil adalah kontak antara ibu hamil dan petugas
kesehatan yang memberikan pelayanan antenatal standar untuk mendapatkan
pemeriksaan kehamilan. Istilah kunjungan tidak mengandung arti bahwa selalu
ibu hamil yang datang ke fasilitas pelayanan, tetapi dapat sebaliknya, yaitu ibu
hamil yang dikunjungi petugas kesehatan di rumahnya atau di posyandu.
Adapun jadwal pemeriksaan kehamilan adalah :
a. Minimal 1 kali pada trimester I (sebelum 14 minggu)
b. Minimal 1 kali pada trimester II (antara minggu 14-28)
c. Minimal 2 kali pada trimester III. (antara minggu 28-36 dan
sesudah minggu ke-36).
Menurut depkes RI (2002) pemeriksaan kehamilan berdasarkan kunjungan
antenatal dibagi atas :
a. Kunjungan pertama (K1) :
Kunjungan K1 adalah kontak ibu hamil yang pertama kali dengan
petugas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan kehamilan dan
pelayanan kesehatan trimester I, dimana usia kehamilan 1 sampai 12
minggu. Kunjungan pertama ini meliputi :
1) Identitas /biodata
2) Riwayat kehamilan
3) Riwayat kebidanan
4) Riwayat kesehatan
5) Riwayat sosial ekonomi

6) pemeriksaan kehamilan dan pelayanan kesehatan
7) Penyuluhan dan konsultasi.
b. Kunjungan keempat(K4):
Kunjungan K4 adalah kontak ibu hamil yang keempat atau lebih
dengan petugas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan kehamilan
dan pelayanan kesehatan pada trimester III, usia kehamilan > 24
minggu.
Kunjungan K4 ini meliputi :
1) Anamnesa keluhan/masalah
2) Pemeriksaan kehamilan dan pelayanan kesehatan
3) Pemeriksaan psikologis
4) Pemeriksaan laboratorium bila ada indikasi/diperlukan
5) Diagnosa akhir (kehamilan normal, terdapat penyulit, terjadi
komplikasi, atau tergolong kehamilan resiko tinggi)
6) Sikap dan rencana tindakan (persiapan persalinan dan rujukan).
5. Standar Pemeriksaan ANC (antenatal care)
1. Pemeriksaan kehamilan dilaksanakan sesuai standar 7T yaitu:
a. (Timbang) berat badan
Ibu hamil yang melakukan kunjungan harus ditimbang berat
badannya. Penimbangan berat badan dilakukan tanpa sepatu dan
memakai pakaian yang seringan-ringannya. Selain menimbang
berat badan, tinggi badan dan ibu hamil juga harus diukur.
Pengukuran dilakukan dengan meteran dengan satuan cm, tanpa
sepatu. Tinggi yang kurang dari 145 cm, ada kemungkinan dapat
mempengaruhi proses persalinan CPD (Cephalo Pelvic
disproportion) (Burns, 2000).
Cara yang dipakai untuk menentukan berat badan menurut
tinggi badan adalah menggunakan indeks massa tubuh (IMT)
dengan rumus berat badan dibagi tinggi badan pangkat 2. Contoh,

wanita dengan BB sebelum hamil 51 kg dan tinggi badan 157
meter. Maka IMTnya 51/(1,57)2 = 20,7.
Nilai IMT mempunyai rentang :
1) <19,8 (underweight)
2) 19,8-26,6 (normal)
3) 26,6-29,0 (overweight)
4) >29,0 (obese).
Penambahan berat badan per trimester lebih penting daripada
penambahan berat badan keseluruhan. Pada trimester pertama
peningkatan berat badan hanya sedikit, 0,7 – 1,4 kg. Pada trimester
berikutnya akan terjadi peningkatan berat badan yang dapat
dikatakan teratur, yaitu 0,35-0,4 kg per minggu (Salmah, 2006).
b. Ukur (Tekanan) darah
Tekanan darah perlu diukur untuk mengetahui perbandingan
nilai dasar selama masa kehamilan. Beberapa kondisi yang dapat
menimbulkan nilai tinggi palsu pada sistolik adalah ketika ibu
merasa cemas atau kandung kemih penuh. Tekanan darah diukur
harus dalam keadaan rileks (Salmah, 2006).
Tekanan darah normal untuk ibu hamil adalah 110/80 – 130/90
mmHg. Bila lebih dari ukuran tersebut, kemungkinan dapat
menyebabkan preeklampsia. Preeklampsia merupakan salah satu
penyebab kematian ibu dan bayi dengan gejala tekanan darah
meningkat, bengkak di kaki dan di tungkai atau seluruh tubuh ibu
hamil jika gangguannya lebih berat (Solihah, 2005).
Tekanan darah yang adekuat diperlukan untuk
mempertahankan fungsi plasenta, tetapi tekanan darah sistolik 140
mmHg atau diastolik 90 mmHg pada saat awal pemeriksaan
mengindikasikan potensi hipertensi dan membutuhkan pemantauan
ketat selama kehamilan (Salmah, 2006).

c. Ukur (Tinggi) fundus uteri
Pemeriksaan lain adalah mengukur tinggi fundus uteri dengan
perabaan. Cara pemeriksaan ini menurut Leopold dibagi dalam 4
tahap yaitu Leopold I, II, III dan IV. Maksud pemeriksaan Leopold
I untuk menentukan tinggi fundus uteri untuk mengetahui tuanya
kehamilan. Tua kehamilan disesuaikan dengan hari pertama haid
terakhir. Selain itu, dapat pula ditentukan bagian janin mana yang
terletak pada fundus uteri. Bila kepala, akan teraba benda bulat dan
keras, sedangkan bokong tidak bulat dan lunak.
Pada Leopold II ditentukan batas samping uterus dan dapat
ditentukan letak punggung janin yang membujur dari atas ke bawah
menghubungkan bokong dengan kepala. Pada letak lintang dapat
ditentukan kepala. Pada letak lintang dapat ditentukan kepala janin.
Pada Leopold III dapat ditentukan bagian apa yang terletak di
sebelah bawah. Sedangkan Leopold IV, selain menentukan bagian
janin mana yang terletak di sebelah bawah, juga dapat menentukan
berapa bagian dari kepala telah masuk ke dalam pintu atas panggul
(Wiknjosastro, 2005).
Gambar 1 : ukur tinggi fundus uteri

Gambar 2 : pemeriksaan Leopold 1- 4
d. Pemberian imunisasi (Tetanus Toxoid)
Pada saat pemeriksaan kehamilan ini ibu hamil diberi suntikan
tetanus toxoid (TT). Pemberian vaksin (toxoid) melalui suntikan,
diperlukan untuk melindungi ibu hamil saat bersama bayinya
terhadap tetanus neonatorum (tetanus saat nifas). Sosialisasi dan
pengertian tentang pemberian TT diperlukan untuk menghindari
fitnah yang luas beredar seolah-olah TT merupakan suntikan
Keluarga Berencana (KB), sehingga ibu hamil menjadi tidak subur
lagi setelah melahirkan (Achsin, 2003).
Ibu hamil yang belum pernah mendapat imunisasi TT pada
kehamilan sebelumnya atau pada waktu akan menjadi pengantin,
maka perlu mendapat dua kali suntikan TT dengan jarak minimal
satu bulan. Imunisasi TT yang pertama diberikan pada kunjungan

antenatal yang pertama. Bila sudah pernah, maka cukup diberikan
sekali selama kehamilan. Suntikan TT melindungi ibu dan bayinya
dari penyakit tetanus neonatorum (Salmah, 2006).
Setiap ibu hamil harus mengetahui dan memahami manfaat
pemberian TT ini, khususnya bila mereka tiba-tiba harus bersalin di
luar jangkauan rumah sakit / rumah sakit bersalin, dokter atau
bidan dan terpaksa ditolong dukun bersalin. Meskipun saat ini
dukun bersalin umumnya telah terlatih untuk menolong persalinan
normal secara steril sehingga tetanus dapat dicegah, tetapi di lain
pihak, rasa kekuatiran pertolongan secara tradisional harus tetap
diperhitungkan. Pemberian TT pada ibu hamil dimaksudkan untuk
memberi kekebalan terhadap tetanus untuk dirinya dan janin dalam
kandungannya (Achsin, 2003).
Gambar 3 : jadwal pemberian imunisasi TT
e. Pemberian (Tablet zat besi), minimum 90 tablet selama
kehamilan
Zat besi penting untuk mengompensasi peningkatan volume
darah yang terjadi selama kehamilan, dan untuk memastikan
pertumbuhan dan perkembangan janin yang adekuat. Kebutuhan
akan zat besi meningkat selama kehamilan, seiring dengan
pertumbuhan janin. Ibu hamil dapat memenuhi kebutuhan zat
besinya yang meningkat selama kehamilan dengan meminum
tablet tambah darah, dan dengan memastikan bahwa ia makan

dengan cukup dan seimbang. Makanan yang mengandung banyak
zat besi antara lain daging, terutama hati dan jeroan, telur, polong
kering, kacang tanah, kacang-kacangan, dan sayuran berdaun hijau
seperti bayam, sawi ijau, dan lain-lain (Pusdiknakes, 2003).
Tanpa persediaan zat besi yang cukup, ibu dapat mengalami
anemia. Ibu yang anemia akan cenderung mengalami kelahiran
prematur, jatuh sakit (karena pertahanan yang lemah terhadap
infeksi), melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah
perdarahan pasca salin, dan meninggal. Banyak ibu-ibu yang sudah
mengalami anemia saat ia hamil. Jarak kehamilan terlalu dekat,
malaria, cacing tambang, dan infeksi yang sering dan kronis,
adalah beberapa penyebab anemia (Achsin, 2003).
Untuk meningkatkan persediaan zat besi selama kehamilan,
semua ibu harus minum tablet tambah darah. Berikan setiap ibu
paling sedikit 90 tablet. Ibu harus meminum satu tablet tambah
darah setiap hari selama kehamilannya. Salah satu efek samping
dari penggunaan zat besi adalah sembelit. Bidan seharusnya
memberikan konseling kepada ibu bahwa mereka akan mengalami
sembelit. Untuk mencegah atau mengurangi sembelit, sebaiknya
bidan mengajarkan ibu untuk mengkonsumsi makanan berserat,
banyak minum air putih, dan melakukan senam (exercise) setiap
hari. (Pusdiknakes, 2003).
Pemberian vitamin zat besi Di mulai dengan memberikan satu
sehari sesegera mungkin setelah rasa mual hilang. Tiap tablet
mengandung FeSO4 320 M (zat besi 60 Mg) dan asam folat 500
Mg, minimal masing-masing 120 tablet. Tablet besi sebaiknya
tidak di minum bersama teh atau kopi, karena mengganggu
penyerapan. Zat besi paling baik di konsumsi di antara waktu
makan bersama jus jeruk (vitamin C).

f. (Tes) terhadap penyakit menular sexual
Penyakit menular seksual (PMS) adalah infeksi yang ditularkan
dari satu orang ke orang lain melalui hubungan seksual. Apapun
bentuk hubungan seksual tersebut bisa menyebabkan PMS.
Kadang-kadang PMS juga bisa terjadi hanya karena saling
menyentuh genitalia yang terinfeksi PMS. PMS bisa ditularkan
dari ibu hamil ke bayi yang dikandungnya sebelum dilahirkan atau
sewaktu melahirkan.
Pemeriksaan PMS dilakukan pada ibu yang mengeluh pada
fungsi organ seksualnya, seperti terjadinya keputihan, gatal pada
daerah kelamin, dan pencegahan terhadap penyakit infeksi menular
seksual yang berbahaya seperti HIV/AIDS.
Terdapat beberapa jenis tes / pemeriksaan yang bisa
memperlihatkan apakah seorang wanita terkena infeksi jenis PMS
tertentu. Tetapi tes-tes tersebut hanya tersedia di tempat terbatas,
dan kadang-kadang tes tersebut tidak memberikan hasil yang
akurat atau tidak mendeteksi semua jenis PMS, disamping itu juga
mahal (Burns, 2000).
g. (Temu wicara) dalam rangka persiapan rujukan.
Seorang bidan, akan bertanya tentang riwayat kehamilan dan
persalinan sebelumnya, termasuk berbagai masalah kesehatan lain
seperti perdarahan atau bayi yang telah meninggal. Keterangan ini
akan membantu untuk mempersiapkan masalah yang sama pada
kehamilan kali ini. Dengan temu wicara, bidan dapat membantu
memastikan ibu untuk makan dengan baik dan memberi nasehat
makanan bergizi; Memberikan tablet zat besi dan asam folat, untuk
mencegah anemia; Memeriksa ibu, untuk memastikan kesehatan
ibu dan bahwa bayi berkembang dengan baik; Memberi vaksinasi
anti tetanus; memberikan obat pencegah malaria, dan memberikan
pemeriksaan laboratorium HIV/AIDS, dan shypilis (Burns, 2000).

7. Pemeriksaan Ibu hamil meliputi:
1. Anamnesis
Anamnesis berupa pertanyaan terarah yang ditujukan kepada ibu
hamil, untuk mengetahui keadaan ibu dan faktor resiko yang
dimilikinya. Pertanyaan yang diajukan dalam anamnesis adalah:
a. Nama, umur, pekerjaan, pendidikan, nama suami, agama, dan
alamat.
b. Keluhan Utama: apakah penderita datang untuk pemeriksaan
kehamilan ataukah ada pengaduan- pengaduan lain yang
penting.
c. Tentang Haid: haid teratur atau tidak, lamanya haid, banyaknya
darah, sifatnya darah, haid nyeri atau tidak, dan haid terakhir.
d. Status perkawinan
e. Kehamilan, persalinan, dan nifas yang lalu jika bukan
kehamilan yang pertama. Kehamilan sekarang: Hal-hal yang
berkaitan dengan kehamilan sekarang yaitu berhubungan
dengan gerakan janin, hal-hal yang dirasakan akibat
perkembangan kehamilan dan penyimpangan dari normal
(keadaan patologis).
f. Anamnesis keluarga: adakah penyakit turunan dalam keluarga
(Sastrawinata, 1983)
2. Pemeriksaan Fisik diagnostik
Pemeriksaan fisik pada ibu hamil bertujuan untuk menilai keadaan
umum ibu, status gizi, tingkat kesadaran, serta ada tidaknya kelainan
bentuk badan (Uliyah, 2006). Selain itu pemeriksaan fisik diagnostik
juga meliputi:
a. Takanan Darah
Tekanan darah pada ibu hamil tidak boleh mencapai 140/90
mmHg Bila tekanan darah naik hingga 30 mmHg sistolik dan
15 mmHg diastolik dari tensi sebelumnya maka perlu dicurigai
toxaemia gravidarum.

b. Berat badan
Berat badan dalam trimester ketiga tidak boleh bertambah lebih
dari 1kg seminggu atau 3kg dalam sebulan. Penambahan yang
lebih dari batasbatas tersebut disebabkan oleh penimbunan
(retensi) air dan hal ini disebut praoedema.
c. Pemeriksaan Laboratorium
Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan urin (glukosa, zat putih
telur dan
sedimen), darah (Hemoglobin, golongan darah), Feses (adakah
telur-telur
cacing).
3. Pemeriksaan Obstetrik
a. Inspeksi
Inspeksi dilakukan untuk menilai keadaan ada tidaknya
cloasma gravidarum pada muka/wajah, pucat atau tidak pada
selaput mata, ada tidaknya oedem. Pemeriksaan selanjutnya
adalah melihat leher, dada, perut, dan pemeriksaan ekstremitas
untuk melihat ada tidaknya varises.
b. Palpasi
Digunakan untuk menentukan besarnya rahim dengan
menentukan usia kehamilan serta menentukan letak anak dalam
rahim. Pemeriksaan secara palpasi dilakukan dengan
menggunakan metode leopold.
c. Auskultasi
Dilakukan umumnya dengan stetoskop monoaural untuk
mendengarkan bunyi jantung anak, bising tali pusat, gerakan
anak, bising rahim, bunyi aorta serta bising usus. Bunyi jantung
anak dapat didengar pada akhir bulan ke-5. Dalam keadaan
sehat bunyi jantung antara 120-140 x/menit. (Uliyah, 2006).

8. Pelaksana dan Tempat Pelayanan Antenatal Care (ANC)
Pelaksana pelayanan antenatal adalah dokter, bidan (bidan
puskesmas, bidan di desa, bidan di praktek swasta), pembantu bidan,
perawat yang sudah dilatih dalam pemeriksaan kehamilan (Depkes RI,
2002).
Pelayanan Antenatal Care dapat dilaksanakan di Puskesmas,
Puskesmas pembantu, posyandu, bidan praktek, polindes, rumah sakit
bersalin dan rumah sakit umum. (Depkes RI, 2002).
9. Faktor predisposisi dalam pemeriksaan Antenatal Care (ANC)
1. Umur
Umur mempunyai pengaruh terhadap kehamilan dan persalinan
ibu. Usia yang kemungkinan tidak resiko tinggi pada saat kehamilan
dan persalinan yaitu umur 20-35 tahun, karena pada usia tersebut rahim
sudah siap menerima kehamilan, mental sudah matang dan sudah
mampu merawat bayi dan dirinya. Sedangkan umur < 20 tahun dan >
35 tahun merupakan umur yang resiko tinggi terhadap kehamilan dan
persalinan. Dengan demikian diketahui bahwa umur ibu pada saat
melahirkan turut berpengaruh terhadap morbiditas dan mortalitas ibu
maupun anak yang dilahirkan.
Ibu yang berumur kurang dari 20 tahun rahim dan bagian tubuh
lainnya belum siap untuk menerima kehamilan dan cenderung kurang
perhatian terhadap kehamilannya. Ibu yang berumur 20-35 tahun rahim
dan bagian tubuh lainnya sudah siap untuk menerima dan diharapkan
untuk memerhatikan kehamilannya. Ibu yang berumur lebih dari 35
tahun rahim dan bagian tubuh lainnya fungsinya sudah menurun dan
kesehatan tubuh ibu tidak sebaik saat berumur 20-35 tahun.

2. Pendidikan
Pendidikan secara umum adalah segala upaya yang
direncanakan untuk memengaruhi orang lain baik individu, kelompok
atau masyarakat sehingga melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku
pendidikan. Pendidikan kesehatan adalah aplikasi atau penerapan
pendidikan didalam bidang kesehatan (Notoatmojo, 2003).
Pendidikan merupakan salah satu unsur penting yang dapat
memengaruhi keadaan keluarga karena dengan tingkat pendidikan yang
lebih tinggi diharapkan pengetahuan atau informasi tentang
pemanfaatan pelayanan kesehatan akan lebih baik. Pengetahuan
kesehatan akan berpengaruh kepada perilaku seseorang sebagai hasil
jangka menengah dari pendidikan yang diperoleh. Perilaku kesehatan
akan berpengaruh pada meningkatnya indikator kesehatan masyarakat
sebagai hasil dari pendidikan kesehatan.
Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi bagaimana seseorang
untuk bertindak dan mencari penyebab serta solusi dalam hidupnya.
Orang yang berpendidikan tinggi biasanya akan bertindak lebih
rasional. Oleh karena itu orang yang berpendidikan akan lebih mudah
menerima gagasan baru.
Ketidakmengertian ibu dan keluarga terhadap pentingnya
pemeriksaan kehamilan berdampak pada ibu hamil tidak memeriksakan
kehamilannya pada petugas kesehatan (Depkes RI, 2008). Sebaliknya
ibu yang berpendidikan tinggi akan memeriksakan kehamilannya secara
teratur demi menjaga keadaan kesehatan dirinya dan anak dalam
kandungannya.
3. Paritas
Menurut Wiknjosastro (2005), paritas 2-3 merupakan paritas
paling aman ditinjau dari sudut kematian maternal. Paritas 1 dan paritas
tinggi (lebih dari 3) mempunyai angka kematian maternal lebih tinggi.
Makin tinggi paritas ibu maka makin kurang baik endometriumnya. Hal
ini diakibatkan oleh vaskularisasi yang berkurang ataupun perubahan

atrofi pada desidua akibat persalinan yang lampau sehingga dapat
mengakibatkan terjadinya plasenta previa. Ibu yang pernah melahirkan
mempunyai pengalaman tentang Antenatal Care (ANC), sehingga dari
pengalaman yang terdahulu kembali dilakukan untuk menjaga
kesehatan kehamilannya (Depkes RI, 2008).
C. Kepatuhan
Kepatuhan merupakan tindakan yang berkaitan dengan perilaku seseorang.
Perilaku manusia hakekatnya merupakan aktivitas dari manuia itu sendiri.
sedangkan tingkat kepatuhan adalah pengukuran pelaksanaan kegiatan yang
sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan. Berdasarkan beberapa
pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan merupakan ketaatan
seseorang untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitas seperti yang disarankan
oleh orang lain.
Perhitungan tingkat kepatuhan dapat sebagai kontrol bahwa pelaksana
program telah melaksanakan program sesuai standar. Dalam hal ini kepatuhan
kunjungan dapat diartikan ketaatan dan tindakan yang berkaitan dengan perilaku
seseorang. Sedangkan kepatuhan kunjungan Antenatal Care dapat diartikan
ketaatan dalam berkunjung ke tempat pelayanan kesehatan oleh ibu hamil sesuai
dengan saran petugas kesehatan dalam hal ini bidan ataupun dokter spesialis
sesuai dengan standar Antenatal Care yang ditetapkan. Bila ibu tidak melakukan
kunjungan sesuai dengan standar tersebut dapat dikatakan bahwa ibu tersebut
tidak patuh dalam melakukan kunjungan Antenatal Care.
1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Melakukan
Antenatal car
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ibu hamil sehingga tidak
memeriksakan kehamilannya diantaranya adalah (Wibowo,1992 dalam
Maulina,2010):
a. faktor akses terhadap pelayanan (jarak, tempat, waktu)
b. faktor sosial ibu hamil ( pendidikan, pengetahuan, sikap)

c. faktor keadaan ekonomi keluarga, faktor reproduksi ibu hamil (paritas,
jarak kelahiran)
d. faktor kondisi kesehatan ibu hamil, faktor pencarian pengobatan.(1)
Selain itu, Anderson (1974) mengembangkan model sistem
kesehatan berupa model kepercayaan kesehatan (health belief model) yang
didasarkan teori lapangan (field theory) dari Lewin (1994). Dalam model
Anderson ini, terdapat 3 (tiga) kategori utama dalam pelayanan kesehatan
yaitu :
1) Komponen predisposisi, menggambarkan kecenderungan
individu yang berbeda-beda dalam menggunakan pelayanan
kesehatan seseorang. Komponen terdiri dari:
a. Faktor-faktor demografi (umur, jenis kelamin, status
perkawinan, besar keluarga dan lain-lain)
b. Faktor struktural sosial (suku bangsa, pendidikan
dan pekerjaan)
c. Faktor keyakinan/kepercayaan (pengetahuan, sikap
dan persepsi)
2) Komponen enabling (pemungkin/pendorong), menunjukkan
kemampuan individual untuk menggunakan pelayanan
kesehatan. Di dalam komponen ini termasuk faktor-faktor
yang berpengaruh dengan perilaku pencarian :
a. Sumber keluarga (pendapatan/penghasilan,
kemampuan membayar pelayanan, keikutsertaan
dalam asuransi, dukungan suami, informasi
pelayanan kesehatan yang dibutuhkan).
b. Sumber daya masyarakat (suatu pelayanan,
lokasi/jarak transportasi dan sebagainya).
3) Komponen need (kebutuhan), merupakan faktor yang
mendasari dan merupakan stimulus langsung bagi individu
untuk menggunakan pelayanan kesehatan apabila faktor-

faktor predisposisi dan enabling itu ada. Kebutuhan pelayanan
kesehatan dapat dikategorikan menjadi :
a. Kebutuhan yang dirasakan/persepsikan (seperti
kondisi kesehatan, gejala sakit, ketidakmampuan
bekerja)
b. Evaluasi/clinical diagnosis yang merupakan
penilaian keadaan sakit didasarkan oleh petugas
kesehatan (tingkat beratnya penyakit dan gejala
penyakit menurut diagnosis klinis dari dokter).
2. Dampak Ketidakpatuhan Melakukan Antenatal Care (ANC)
Tujuan utama pemeriksaan kehamilan (Antenatal Care) adalah
untuk memfasilitasi hasil yang sehat dan positif bagi ibu maupun bayinya
dengan cara membina hubungan saling percaya dengan ibu, mendeteksi
komplikasi yang dapat mengancam jiwa, mempersiapkan kelahiran dan
memberikan pendidikan. Sehingga bila ANC tidak dilakukan sebagaimana
mestinya maka akan mengakibatkan dampak:
1. Ibu hamil kurang mendapat informasi tentang cara perawatan
kehamilan yang benar,
2. Tidak terdeteksinya tanda bahaya kehamilan secara dini,
3. Tidak terdeteksinya anemia kehamilan yang dapat
menyebabkan perdarahan saat persalinan,
4. Tidak terdeteksinya tanda penyulit persalinan sejak awal
seperti kelainan bentuk panggul atau kelainan pada tulang
belakang, atau kehamilan ganda,
5. Tidak terdeteksinya penyakit penyerta dan komplikasi selama
kehamilan seperti preeclampsia, penyakit kronis (penyakit
jantung atau paru), dan penyakit karena genetic (diabetes,
hipertensi, atau cacat congenital).

Sehingga bila tidak ditangani atau tidak dilakukan skrining sejak
awal, akan mengakibatkan komplikasi pada saat hamil atau pada saat
persalinan yang akan mengarah kepada kematian baik ibu maupun janin
D. PUSKESMAS
1. Definisi
Puskesmas adalah unit pelaksanan teknis dinas kesehatan
kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan
pembangunan kesehatan di wilayah kerja (KEPMENKES RI, 2004)
Pengertian pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas)
menunjukkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan
perkembangan dan tuntutan pelayanan kesehatan dewasa ini, tempat
puskesmas menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat
menyeluruh, terpadu, dan merata dapat diterima dan dijangkau
masyarakat dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan
hasil pengambangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna
dengan biaya yang dipikul oleh pemerintah dan masyarakat luas guna
mencapai derajat kesehatan yang optimal tanpa mengabaikan mutu
pelayanan kepada perorangan.
2. Konsep dasar Puskesmas
Puskesmas adalah unit pelaksanaan teknis dinas kesehatan
kabupaten/kota yang bertanggung jawab untuk melenggarakan
pembangunan kesehatan di wilayah kerja. Disebut unit pelaksana
teknis karena merupakan unit pelaksanan tingkat pertama dan berperan
sebagai penyelengara sebagian tugas teknis operasional dinas
kesehatan kabupaten/kota serta sebagai ujung tombak pembangunan
kesehatan Indonesia.

3. Fungsi Puskesmas
a. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan
b. Pusat pemberdayaan masyarakat
c. Pusat pelayanan kesehatan strata pertama
1. Pelayanan kesehatan perorangan (private goods)
2. Pelayanan kesehatan masyarakat (public goods)
4. Upaya kesehatan Puskesmas
1) Upaya kesehatan wajib
a. Upaya promosi kesehatan
b. Upaya kesehatan lingkungan
c. Upaya kkesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana
d. Upaya perbaikkan gizi masyarakat
e. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
f. Upaya pengobatan
2) Upaya kesehatan pengembangan
a. Upaya kesehatan sekolah
b. Upaya kesehatan olahraga
c. Upaya perawatan kesehatan masyarakat
d. Upaya kesehatan kerja
e. Upaya kesehatan gigi dan mulut
f. Upaya kesehatan jiwa
g. Upaya kesehatan mata
h. Upaya kesehatan usia lanjut
i. Upaya pembinaan pengobatan tradisional

E. SISTEM RUJUKAN
1) Definisi
Suatu sistem jaringan fasilitas pelayanan kesehatan yang
memungkinkan terjadinya penyerahan tanggung jawab secara timbale
balik atas masalah yang timbul baik secara vertical maupun horizontal ke
fasilitas pelayanan yang lenih kompeten.
2) Tujuan rujukan
a. Dihasilkannya pemerataan upaya kesehatan yang didukung
mata pelayanan yang optimal dalam rangka memecahkan
masalah kesehatan secara berdaya dan berhasil guna
b. Dihasilkannya upaya pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif
dan rehabilitatif.
c. Dihasilkannya upaya pelayanan kesehatan yang bersifat
preventif dan promotif.
3) Jenis rujukan
a. Rujukan medik yaitu pelimpahan tanggungjawab secara timbal
balik atas satu kasus yang timbul baik secara vertical maupun
horizontal kepada yang lebih berwenang dan mampu
menanganinya secara rasional. Jenis rujukan medik :
1. Transfer of specimen : pengiriman bahan (spesimen)
untuk pemeriksaan laboratorium lebih lengkap
2. Transfer of patient : konsultasi penderita untuk keperluan
diagnose, pengobatan, tindakan operatif dan lain-lain.
3. Transfer of knowledge : pengiriman tenanga yang lebih
kompeten atau ahli untuk meningkatkan mutu layanan
pengobatan setempat.
b. Rujukan kesehatan yaitu hubungan dalam pengiriman,
pemeriksaan bahan atau specimen ke fasilitas yang lebih mampu
dan lengkap. Ini adalah rujukan yang menyangkut masalah
kesehatan yang sifatnya preventif dan promotif. Tujuan sistem
rujukan adalah untuk meningkat mutu,cakupan dan efisiensi

pelayanan kesehatan secara terpadu. Dengan adanya sistem rujukan
diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih
bermutu karena tindakan rujukan dapat menjadi factor yang
menentukan untuk menurunkan angka kematian ibu dan perinatal,
terutama dalam mengatasi keterlambatan.
Persiapan saat melakukan rujukan, meliputi persiapan yang akan
menemani ibu atau bayi baru lahir, tempat rujukan, sarana transportasi
yang akan digunakan, orang yang akan ditunjuk untuk menjadi donor
darah, dana serta siapa yang akan tinggal dan menemani anak yang lain
pada saat ibu tidak dirumah atau disingkat menjadi BAKSO (Bidan, Alat,
Keluarga, Surat, Obat, Kendaraan dan Uang).

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Jenis penelitian :
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif
retrospektif.
3.2 Lokasi penelitian :
Penelitian dilaksanakan di wilayah Puskesmas Sentani, Kecamatan
Sentani, Kelurahan Sentani kota
3.3 Waktu penelitian :
Bulan Juni- Agustus 2013
3.4 Populasi dan sampel penelitian :
Populasi :
Populasi pada pnilitian ini adalah semua ibu hamil yang
berkunjung untuk memeriksakan kehamilannya pada periode Juni 2012 –
Juni 2013.
Sampel :
Sampel yang diambil pada penilitian ini yaitu total populasi
sebanyak 60 orang ibu hamil
3.5 Variabel yang diteliti :
1. Umur
2. Pendidikan
3. Paritas

3.6 Definisi operasional :
1. Usia : yang dimaksud umur ibu hamil yang dihitung sejak lahir sampai
berkunjung ke Puskesmas.
Umur ibu hamil dikelompokkan berdasarkan tingkat kedewasaan :
1) Umur < 20 tahun atau > 35 tahun = beresiko
2) Umur 20-35 tahun = tidak beresiko
2. Pendidikan : pendidikan adalah suatu proses dimana pengalaman atau
informasi diperoleh sebagai hasil dari proses belajar. Pada umumnya
semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin baik pula tingkat
pengetahuannya (Notoatmodjo, 2003). Pendidikan yang dimaksud
adalah jenjang pendidikan terakhir ibu
1) Tidak sekolah
2) SD – SMP
3) SMA – Perguruan tinggi
3. Paritas : yang dimaksud adalah jumlah persalinan yang dialami ibu
ditinjau dari sudut kematian maternal.
1) 1 = kurang
2) 2-3 = aman
3) 0 atau > 3 = tinggi
3.7 Teknik pengambilan dan pengolahan data
3.7.1 Pengambilan data
Data diambil dengan menggunakan data sekunder yang
diambil dari Rekam Medik
3.7.2 Pengolahan data
Setelah data dikumpulkan kemudian diolah dan disajikan
dalam bentuk tabulasi distribusi frekuensi.