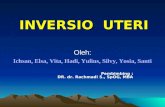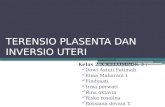INVERSIO UTERUS.docx
-
Upload
septiana-yollandha -
Category
Documents
-
view
58 -
download
4
Transcript of INVERSIO UTERUS.docx

INVERSIO UTERUSA.Pengertian
Inversio uterus adalah keadaan dimana lapisan dalam uterus (endometrium) turun dan keluar lewat ostium uteri eksternum yang dapat bersifat inkomplit sampai komplit .Pada inversion uterus, kalau hanya fundus melekuk ke dalam dan tidak keluar ostium uteri disebut inversion uterus inkomplit/parsial. Iversio uterus yang berputar balik sehingga fundus uteri terdapat dalam vagina dengan selaput lendirnya sebelah luar, keadaan ini disebut inversion uteri komplit/total, sedangkan uterus yang berputar balik, keluar dari vulva disebut inversion prolaps Inversion uteri jarang terjadi berkisar antara 1: 2000 s/d 20000 kehamilan akan tetapi merupakan komplikasi kala tiga persalinan jika terjadi dapat menimbulkan shock berat dan berpotensi membahayakan jiwa.Klasifikasi inversiInversi dapat di klasifikasikan berdasarkan tingkat keparahannya, yaitu :
1. Derajat pertama : fundus mencapai os internal2. Derajat kedua : badan atau korpus uterus mengalami inversi kedalam os internal3. Derajat ketiga : uterus, serviks dan vagina mengalami inversi dan dapat dilihat.
Inverse juga dapat di klasifikasikan berdasarkan waktu terjadinya :1. Inversi akut : terjadi dalam 24 jam pertama 2. Inversi subakut : terjadi setelah 24 jam pertama dan dalam 4 minggu 3. Inversi kronis : terjadi setelah 4 minggu dan jarang terjadi
B. Etiologi Penyebab inversi uteri berkaitan dengan atonia uteri dan dilatasi serviks yang meliputi:
1. Penatalaksanaan yang salah pada kala tiga persalinan termasuk penarikan tali pusat yang berlebihan untuk pelahiran plasenta secara aktif.
Akibat traksi tali pusat dengan plasenta yang berimplantasi di bagian fundus uteri dan di lakukan dengan tenaga berlebihandi luar kontraksi uteru yang menyebabkan inversion uteri.
2. Kombinasi tekanan fundus dan penarikan tali pusat untuk melahirkan plasenta3. Penggunaan tekanan fundus untuk melahirkan plasenta saat uterus atonik4. Perlekatan plasenta yang patologis 5. Terjadinya secara spontan tidak diketahui penyebabnya6. Primiparitas7. Makrosomia janin 8. Tali pusat pendek9. Pengosongan yang tiba-tiba saat uterus mengalami distensi
C. Diagnosis dan gejala klinis inversio uteri 1. Dijumpai pada kala III atau post partum dengan gejala nyeri yang hebat,
perdarahan yang banyak sampai syok. Apalagi bila plasenta masih melekat dansebagian sudah ada yang terlepas dan dapat terjadi strangulasi dan nekrosis.
2. Pemeriksaan dalam

a. Bila masih inkomplit maka pada daerah simfisis uterus teraba fundus utericekung ke dalam.
b. Bila komplit, di atas simfisis uterus teraba kosong dan dalam vagina terabatumor lunak.
c. Kavum uteri sudah tidak ada (terbalik).D.Tanda dan Gejala Inversio uteri ditanda gejalai dengan :
1. Syok karena kesakitan yang mengalami inverse yang diperkirakan terjadi akibat peregangan saraf peritoneum dan ovarium yang tertarik ketika fundus
2. Fundus uteri sama sekali tidak teraba atau teraba lekukan pada fundus 3. Perdarahan yang bisa terjadi bisa tidak, bergantung pada derajat perlekatan plasenta ke dinding
uterus 4. Di vulva tampak endometrium terbalik dengan atau tanpa plasenta yang masih melekat5. Bila baru terjadi prognosis cukup baik akan tetapi bila kejadiannya cukup lama, maka jepitan
serviks yang mengecil akan membuat uterus mengalami iskemia, mekrosis dan infeksi.
E.Penatalaksanaan Secara garis besar penatalaksanaan yang dilakukan untuk inversio uteri adalah sebagai berikut :
1. Memanggil bantuan anestesi dan memasang infus untuk cairan/darah penggantian dan pemberian obat
2. Beberapa senter memberikan tokolitik/ MgSO4 untuk melemaskan uterus yang ter balik sebelum dilakukan reposisi manual yaitu mendorong endometrium ke atas masuk ke dalam vagina dan terus melewati serviks sampai tangan masuk ke dalam uterus pada posisi normalnya. Hal itu dapat dilakukan sewaktu plasenta sudah terlepas atau tidak.
Reposisi manual(a)inversion uteri total (b)revosisi uteru melalui serviks (c)retetusi uterus
3. Didalam uterus plasenta dilepaskan secara manual dan bila berhasil di keluarkan dari rahim dan sambil memberikan uterotonika lewat infuse atau intra muscular tangan tetap di pertahankan agar konfigurasi uterus kembali normal dan tangan operator baru dilepaskan.
4. Pemberian antibiotika dan tranfusi darah sesuai dengan keperluannya

5. Intervensi bedah dilakukan bila karena jepitan serviks yang keras menyebabkan maneuver di atas tidak bisa dikerjakan, maka dilakukan laparotomi untuk reposisi dan kalau terpaksa dilakukan histerektomibila uterus sudah mengalami infeksi dan nekrosis .
Reposisi melalui laparotomi

BAB IIPEMBAHASAN
2.1 PengertianInversio uteri adalah keadaan dimana fundus uteri terbalik sebagianØ atau seluruhnya
masuk ke dalam kavum uteri (Rustam Muchtar. Prof. Dr. MPH, Sinopsis Obstetri, Jilid I, edisi 2 ; 1998).
Inversio uteri adalah suatu keadaan dimana sebagian atas uterus (fundus uteri) memasuki kavum uteri sehingga fundus uteri sebelah dalam menonjol kedalam kavum uteri.(PrawihardjoSarwono, Prof. Dr, Ilmu Kebidanan ; Jakarta)
Inversion uteri merupakan keadaan dimana fundus uteri masuk kedalam kavum uteri,dapat secara mendadak atau perlahan.kajadian ini biasanya disebabkan pada saat melakukan persalinan plasenta secara crede,dengan otot rahim belum berkontraksi dengan baik.inversio uteri memberikan rasa sakit yang dapat menimbulkan keadaan syok.
(menurut dr.ida Bagus Gde manuaba,SpOG)
2.2 Klasifikasi inversio uteriMenurut perkembangannya inversio uteri dapat dibagi dalam beberapa tingkat :
1) Inversio uteri ringanFundus uteri terbalik menonjol dalam kavum uteri, namun belum keluar dari ruang rongga rahim.
2) Inversio uteri sedangFundus uteri terbalik dan sudah masuk dalam vagina.
3) Inversio uteri beratUterus dan vagina semuanya terbalik dan sebagian besar sudah terletak diluar vagina.Ada pula beberapa pendapat membagi inversio uteri menjadi :
1) Inversio inkomplitYaitu jika hanya fundus uteri menekuk ke dalam dan tidak keluar ostium uteri atau serviks uteri.
2) Inversio komplitSeluruh uterus terbalik keluar, menonjol keluar serviks uteri.
2.3 Etiologia) Penyebab Inversio Uteri yaitu :
1. Spontan :grande multipara, atoni uteri, kelemahan alat kandungan, tekanan intra abdominal yang tinggi (mengejan dan batuk).
2. Tindakan :cara Crade yang berlebihan, tarikan tali pusat, manual plasenta yang dipaksakan, perlekatan plasenta pada dinding rahim.b) Faktor yang mempermudah terjadinya inversio uteri :
1. Tunus otot rahim yang lemah2. Tekanan atau tarikan pada fundus (tekanan intra abdominal, tekanan dengan tangan, tarikan pada
talipusat).3. Canalis servikalis yang longgar. 4. Patulous kanalis servikalis.
Akibat traksi tali pusat dengan plasenta yang berimplantasi dibagian fundus uteri dan dilakukan dengan tenaga berlebihan dan diluar kontraksi uterus akan menyebabkan inversio uteri
2.4 Tanda gejala inversio uteri

Gejala klinis inversio uteri:1. Dijumpai pada kala III atau post partum dengan gejala nyeri yang hebat, perdarahan yang banyak sampai
syok.Apalagi bila plasenta masih melekat dan sebagian sudah ada yang terlepas dan dapat terjadi strangulasi dan nekrosis.
2. Pemeriksaan dalam : ± Bilama sihin komplit maka pada daerah simfisis uterus teraba fundus uteri cekung kedalam. ± Bila komplit, di atas simfisis uterus teraba kosong dan dalam vagina teraba tumor lunak. ± Kavum uteri sudah tidak ada (terbalik).Tanda dan gejala inversio uteri yang selalu adaa) Uterus terlihatb) Uterus bias terlihat sebagai tonjolan mengilat, merah lembayung di vaginac) Plasenta mungkin masih melekat (tampak tali pusat)d) PerdarahanTanda paling sering inversio uteri adalah perdarahan,tetapi cepatnya ibu mengalami kolaps dengan jumlah kehilangan darahnya.a) Syok beratb) Nyeri abdomen bawah berat, disebabkan oleh penarikan pada ovarium dan peritoneum serta bias disertai rasa ingin defekasi.c) Lumen vagina terisi massa
2.5 Presentasiinversio uterus mungkin hadir:1. Akut - dalam waktu 24 jam setelah melahirkan 2. Subacutely - lebih dari 24 jam dan sampai 30 hari postpartum3. Kronis - lebih dari 30 hari setelah melahirkan
2.6 DiagnosaDiagnosis biasanya tidak sulit, terutama apabila timbul perdarahan banyak dalam waktu pendek. Tetapi bila perdarahan sedikit dalam jangka waktu lama, tanpa disadari pasien telah kehilangan banyak darah sebelum ia tampak pucat. Nadi serta pernafasan menjadi lebih cepat dan tekanan darah menurun Diagnosis Perdarahan Pascapersalinan.1. Palpasi uterus: bagaimana kontraksi uterus dan tinggi fundus uteri2. Memeriksa plasenta dan ketuban apakah lengkap atau tidak3. Lakukan eksplorasi cavum uteri untuk mencari sisa plasenta atau selaput ketuban4. Robekan rahim5. Plasenta suksenturiata6. Inspekulo: untuk melihat robekan pada serviks, vagina, dan varises yang pecah7. Pemeriksaan Laboratorium periksa darah yaitu Hb, COT (Clot Observation Test), dl
Perdarahan pasca persalinan ada kalanya merupakan perdarahan yang hebat dan menakutkan hingga dalam waktu singkat ibu dapat jatuh kedalam keadaan syok. Atau dapat berupa perdarahan yang menetes perlahan-lahan tetapi terus menerus yang juga bahaya karena kita tidak menyangka akhirnya perdarahan berjumlah banyak, ibu menjadi lemas dan juga jatuh dalam presyok dan syok. Karena itu, adalah penting sekali pada setiap ibu yang bersalin dilakukan pengukuran kadar darah secara rutin, serta pengawasan tekanan darah, nadi, pernafasan ibu, dan periksa juga kontraksi uterus perdarahan selama 1 jam.

2.7 PenangananPencegahan Inversi Sebelum Tindakan :
1. Koreksi Manuala) Pasang sarung tangan DTTb) Pegang uterus pada daerah insersi tali pusat dan masukkan kembali melalui serviks.Gunakan tangan lain untuk membantu menahan uterus dari dinding abdomen.Jika plasenta masih belum terlepas,lakukan plasenta manual setelah tindakan koreksi.masukkan bagian fundus uteri terlebih dahulu.c) Jika koreksi manual tidak berhasil,lakukan koreksi hidrostatik.
2. Koreksi Hidrostatika) Pasien dalam posisi trendelenburg dengan kepala lebih rendah sekitar 50 cm dari perineum.b) Siapkan sistem bilas yang sudah desinfeksi,berupa selang 2 m berujung penyemprot berlubang
lebar.Selang disambung dengan tabung berisi air hangat 2-5 l(atau NaCl atau infus lain) dan dipasang setinggi 2 m.
c) Identifikasi forniks posterior.d) Pasang ujung selang douche pada forniks posterior sampai menutup labia sekitar ujung selang
dengan tangan.e) Guyur air dengan leluasa agar menekan uterus ke posisi semula.
3. Koreksi Manual Dengan Anestesia Umuma) Jika koreksi hidrostatik gagal,upayakan reposisi dalam anastesia umum. Halotan merupakan pilihan untuk relaksasi uterus.
4. Koreksi Kombinasi Abdominal – VaginalØa) Kaji ulang indikasib) Kaji ulang prinsip dasar perawatan operatifc) Lakukan insisi dinding abdomen sampai peritoneum,dan singkirkan usus dengan kasa.tampak uterus berupa lekukan.d) Dengan jari tangan lakukan dilatasi cincin konstriksi serviks.e) Pasang tenakulum melelui cincin serviks pada fundus.f) Lakukan tarikan atau traksi ringan pada fundus sementara asisten melakukan koreksi manual melalui vagina.g) Jika tindakan traksi gagal,lakukan insisi cincin kontriksi serviks di bagian belakang untuk menghindari resiko cedera kandung kemih,ulang tindakan dilatasi,pemasangan tenakulum dan fraksi fundus.h) Jika koreksi berhasil,tutup dinding abdomen setelah melakukan penjahitan hemostasis dan dipastikan tidak ada perdarahan.i) Jika ada infeksi ,pasang drain karet.

BAB 2
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian
Inversio uteri adalah suatu keadaan dimana bagian atas uterus (fundus uteri) memasuki
cavum uteri sehingga fundus uteri sebelah dalam menonjol ke dalam kavum uteri bahkan
kedalam vagina atau keluar vagina dengan dinding endometriumnya sebelah luar. (Sarwono
Prawirohardjo,2009;442)
Inversio uteri adalah terbaliknya fundus uteri ke dalam kavum uteri yang dapat
menimbulkan nyeri dan perdarahan. (Manuaba,2008;171)
Inversio Uteri adalah suatu keadaan dimana badan rahim berbalik, menonjol melalui
serviks (leher rahim) ke dalam atau ke luar vagina. (FK UNPAD, 2003;238)
Inversio uteri merupakan keadaan dimana bagian atas uterus memasuki kavum uteri,
sehingga fundus uteri sebelah dalam menonjol kedalam kavum uteri. Peristiwa ini jarang sekali
ditemukan, terjadi tiba-tiba dalam kala III/ segera setelah plasenta keluar.
2.2 Derajat
1. Derajat Pertama
Inverso uteri hanya sampai ostium uteri internum. Teraba fundus uterinya hilang atau
terdapat lekukan
2. Derajat kedua
Seluruh endometrium terbalik, tetapi tidak sampai luar perineum. Fundus uteri hilang saat
palpasi.
3. Derajat Ketiga
Seluruh endometrium terbalik sampai tampak diluar perineum dan dapat disertai plasenta
yang masih melekat. Fundus uteri sama sekali tidak dapat diraba.
2.3 Penyebab
1. Pada Grandemultipara karena terjadi atonia uteri
2. Tali Pusat terlalu pendek

3. Tarikan tali pusat terlalu keras sedangkan kontraksi uterus belum siap untuk melahirkan
plasenta.
4. Pelaksanaan perasat crede, saat kontraksi uterus belum siap untuk mendorong plasenta lahir
5. Plasenta terlalu erat melekat pada tempat implantasinya.
6. Tonus otot rahim yang lemah
7. Canalis servikalis yang longgar
2.4 Tanda dan Gejala
Rasa nyeri yang hebat dan dapat menimbulkan syok. Rasa nyeri yang hebat tersebut disebabkan
karena fundus uteri menarik adneksa serta ligamentum infundibulopelvikum dan ligamentum
rotundum kanan dan kiri ke dalam terowongan inversio sehingga terjadi tarikan yang kuat pada
peritoneum parietal.
Perdarahan yang banyak akibat dari plasenta yang masih melekat pada uterus, hal ini dapat juga
berakibat syok .
2.5 Diagnosa
Diagnose juga bisa ditegakkan apabila pemeriksa menemukan beberapa tanda inversi
uterus yang mencakup:
Uterus menonjol dari vagina.
Fundus tidak tampaknya berada dalam posisi yang tepat ketika dokter palpasi (meraba) perut ibu.
Adanya perdarahan yang tidak normal dan perdarahannya banyak bergumpal.
Tekanan darah ibu menurun (hipotensi).
Ibu menunjukkan tanda-tanda syok (kehilangan darah) dan kesakitan
Di vulva tampak endometrium terbalik dengan atau tanpa plasenta yang masih melekat.
Bila baru terjadi maka, maka prognosis cukup baik akan tetapi bila kejadian cukup lama maka
jepitan serviks yang mengecil akan membuat uterus mengalami iskemia, nekrosis, dan infeksi.
2.4 Penatalaksanaan
1. Pencegahan : hati-hati dalam memimpin persalinan, jangan terlalu mendorong rahim atau
melakukan perasat Crede berulang-ulang dan hati-hatilah dalam menarik tali pusat serta
melakukan pengeluaran plasenta dengan tajam.
2. Bila telah terjadi maka terapinya :
Bila terjadi syok atau perdarahan, gejala ini diatasi dulu dengan infus intravena cairan elektrolit
dan tranfusi darah.

Untuk memperkecil kemungkinan terjadinya renjatan vasovagal dan perdarahan maka harus
segera dilakukan tindakan reposisi secepat mungkin.
Segera lakukan tindakan reposisi
Bila plasenta masih melekat , jangan dilepas oleh karena tindakan ini akan memicu perdarahan
hebat
Salah satu tehnik reposisi adalah dengan menempatkan jari tangan pada fornix posterior, dorong
uterus kembali kedalam vagina, dorong fundus kearah umbilikus dan memungkinkan
ligamentum uterus menarik uterus kembali ke posisi semula . Rangkaian tindakan ini dapat
dilihat pada gambar 1
Sebagai tehnik alternatif : dengan menggunakan 3 – 4 jari yang diletakkan pada bagian tengah
fundus dilakukan dorongan kearah umbilkus sampai uterus kembali keposisi normal.
Setelah reposisi berhasil, tangan dalam harus tetap didalam dan menekan fundus uteri. Berikan
oksitosin atau Suntikkan intravena 0,2 mg ergomitrin kemudian dan jika dianggap masih perlu,
dilakukan tamponade uterovaginal dan setelah terjadi kontraksi, tangan dalam boleh dikeluarkan
perlahan agar inversio uteri tidak berulang.
Bila reposisi per vaginam gagal, maka dilakukan reposisi melalui laparotomi.
PERAWATAN PASCA TINDAKAN
1. Jika inversi sudah diperbaiki, berikan infus oksitoksin 20 unit dalam 500 ml IV (NaCl 0,9 % atau
Ringer Lactat) 10 tetes/menit :
a. Jika dicurigai terjadi perdarahan, berikan infus sampai dengan 60 tetes permenit.
b. Jika kontraksi uterus kurang baik, berikan ergometrin 0,2 mg atau prestaglandin
2. Berikan Antibiotika proflaksis dosis tunggal :
a. Ampisilin 2 gr IV dan metronidazol 500mg IV
b. Sefazolin 1 gr IV dan metranidazol 500 mg IV
3. Lakukan perawatan pasca bedah jika dilakukan koreksi kombinasi abdominal vaginal
4. Jika ada tanda infeksi berikan antibiotika kombinasi sampai pasien bebas demam 48 jam:
a. Ampisilin 2 gr IV tiap 6 jam
b. Gestamin 5 mg/kg berat badan IV setiap 24 jam
c. Metranidazol 500mg IV setiap 8 jam
5. Berikan analgesik jika perlu


BAB II
PEMBAHASAN
A. Defenisi
Mola Hadatidosa menurut para Ahli :
Mola hidatidosa adalah chorionic villi (jonjotan/gantungan) yang tumbuh berganda berupa gelembung-gelembung kecil yang mengandung banyak cairan sehingga menyerupai buah anggur atau mata ikan. Karena itu disebut juga hamil anggur atau mata ikan. (Mochtar, Rustam, dkk, 1998 : 23)
Mola hidatidosa adalah kehamilan abnormal, dengan ciri-ciri stoma villus korialis langka, vaskularisasi dan edematus. Janin biasanya meninggal akan tetapi villus-villus yang membesar dan edematus itu hidup dan tumbuh terus, gambaran yang diberikan adalah sebagai segugus buah anggur. (Wiknjosastro, Hanifa, dkk, 2002 : 339).
Mola hidatidosa adalah perubahan abnormal dari villi korionik menjadi sejumlah kista yang menyerupai anggur yang dipenuhi dengan cairan. Embrio mati dan mola tumbuh dengan cepat, membesarnya uterus dan menghasilkan sejumlah besar human chorionic gonadotropin (hCG) (Hamilton, C. Mary, 1995 : 104).
Mola Hadatidosa secara Umum :
Mola Hidatidosa ditandai oleh kelainan vili korialis, yang terdiri dari proliferasi
trofoblastik dangan derajat yang bervariasi dan edema sroma vilus. Mola biasanya menempati
kavum uteri, tetapi kadang-kadang tumor ini ditemukan dalam tuba falopii dan bahkan dalam
ovarium. Perkembangan penyakit trofoblastik ini amat menarik, dan ada tidaknya jaringan janin
telah digunakan untuk menggolongkannya menjadi bentuk mola yang komplet (klasik) dan
parsial (inkomplet)
Karakteristik Mola Hidatidosa bentuk komplet dan parsial :
Gambaran
Mola parsial
(inkomplet)
Mola Komplet
(klasik)
Jaringan embrio atau janin Ada Tidak ada

Pembengkakan
hidatidosa pada vili Fokal Difus
Hyperplasia
Fokal Difus
Inklusi stroma Ada Tidak ada
Lekukan vilosa Ada Tidak ada
a. Mola Hidatidosa Komplet (klasik)
Vili korialis berubah menjadi kumpulan gelembung yang jernih. Gelembung-gelembung
atau vesikula ini bervariasi ukurannya mulai dari yang mudah terlihat sampai beberapa cm, dan
bergantung dalam beberapa kelompok dari tangkai yang tipis. Massa tersebut dapat tumbuh
cukup besar sehingga memenuhi uterus, yang besarnya bisa mencapai ukuran uterus kehamilan
normal lanjut. Berbagai penelitian sitogenetik terhadap kehamilan mola komplet, menemukan
komposisi kromosom yang paling sering (tidak selalu) 46XX, dengan kromosom sepenuhnya
berasal dari ayah.
Fenomena ini disebut sebagai androgenesis yang khas ovum dibuahi oleh sebuah sperma
haploid yang kemudian mengadakan duplikasi kromosomnya sendiri setelah miosis. Kromosom
ovum bias tidak terlihat atau tampak tidak aktif. Tetapi semua mola hidatidosa komplet tidak
begitu khas dan kadang-kadang pola kromosom pada mola komplet biSA 46XY. Dalam keadaan
ini dua sperma membuahi satu ovum yang tidak mengandung kromosom. Variasi lainnya juga
pernah dikemukakan misalnya 45X. jadi mola hidatidosa yang secara morfologis komplet dapat
terjadi akibat beberapa pola kromosom.
b. Mola Hidatidosa Parsial (inkomplet)
Apabila perubahan hidatidosa bersifat fokal serta belum begitu jauh dan masih terdapat
janin atau sedikitnya kantong amnion, keadaan ini digolongkan sebagai mola hidatidosa parsial.

Pada sebagian vili yang biasanya avaskuler terjadi pembengkakan hidatidisa yang berjalan
lambat, sementara vili lainnya yang vaskular dengan sirkulasi darah fetus plasenta yang masih
berfungsi tidak mengalami perubahan. Hyperplasia trofoblastik yang terjadi, lebih bersifat fokal
dari pada generalisata. Katiotipe secara khas berupa triploid, yang bias 69XXY atau 69XYY
dengan satu komplemen maternal tapi biasanya dengan dua komplemen haploid paternal. Janin
secara khas menunjukkan stigmata triploidi yang mencakup malformasi congenital multiple dan
retardasi pertumbuhan.
B. Tanda dan Gejala
Tanda dan Gejala yang biasanya timbul pada klien dengan ”mola hidatidosa” adalah :
a. Amenore dan tanda-tanda kehamilan
b. Perdarahan pervaginam berulang. Darah cenderung berwarna coklat. Pada
keadaan lanjut kadang keluar gelembung mola.
c. Pembesaran uterus lebih besar dari usia kehamilan.
d. Tidak terabanya bagian janin pada palpasi dan tidak terdengarnya DJJ
sekalipun uterus sudah membesar setinggi pusat atau lebih.
e. Preeklampsia atau eklampsia yang terjadi sebelum kehamilan 24 minggu.
f. hiperemesis lebih sering terjadi, lebih keras dan lebih lama.
g. mungkin timbul preeklampsia dan eklampsia. Terjadinya preeclampsia dan eklampsia
sebelum minggu kedau empat menuju kearah mola hidatidosa.
h.kadar gonadotropin tinggi dalam darah serum pada hari ke 100 atau lebih
sesudah periode menstruasi terakhir.
C. Gambaran Diagnosis
Kita harus mempertimbangkan kemungkinan data-data tentang menstruasi atau uterus
hamil yang lebih lanjut membesar akibat mioma, hidramnion, atau terutama akibat janin lebih
dari satu.

a. Ultrasonografi
Ketapatan diagnostic yang terbesar diperoleh dari gambaran USG yang khas pada mola
hidatidosa keamanan dan ketepatan pada pemeriksaan sonografi membuat pemeriksaan ini
menjadi prosedur pilihan. Tetapi kita harus ingat bahwa beberapa stuktur lainnya dapat
memperlihatkan gambaran yang serupa dengan gambaran mola hidatidosa, termasuk mioma uteri
dengan kehamilan dini dan kehamilan dengan janin lebih dari satu. Tinjauan cermat mengenai
riwayat penyakit bersama hasil evaluasi pemeriksaan USG yang cermat dan kalau perlu diulang
satu atau dua minggu kemudian, harus bias menghindari diagnose mola hidatidosa lewat USG
yang keliru ketika kehamilan sebenarnya normal.
b. Amniografi
Penggunaan bahan radiopak yang dimasukkan kedalam uterus secara transabdominal akan
memberikan gambaran radiografik khas pada mola hidatidosa. Cavum uteri ditembus dengan
jarum untuk amniosintesis. 20ml hypaque disuntikkan segera dan 5 hingga 10 menit kemudian
difoto anteroposterior. Pola sinar x seperti sarang tawon, khas ditimbulkan oleh bahan kontraks
yang mengelilingi gelembung-gelembung corion. Pada kehamilan normal terdapat sedikit resiko
abortus akibat penyuntikan bahan kontraks hipertonik intra amnion. Dengan semakin banyaknya
sarana USG yang tersedia, teknik pemeriksaan amniografi sudah jarang dipakai lagi.
c. Pengukuran kadar corionic gonadotropin
Pengukuran kadar corionic gonadotropin kadang-kadang digunakan untuk membuat
diagnose jika metode pengukuran secara kuantitatif yang andal telah tersedia, dan variasinya
cukup besar pada sekresi gonadotropin dalam kehamilan normal sudah dipahami khusus
kenaikan kadar gonadotropin yang kadang-kadang menyertai kehamilan dengan janin lebih dari
satu.
d. Uji Sonde
Sonde (penduga rahim) dimasukkan pelan-pelan dan hati-hati ke dalam kanalis servikalis dan
kavum uteri. Bila tidak ada tahanan, sonde diputar setelah ditarik sedikit, bila tetap tidak ada
tahanan, kemungkinan mola (cara Acosta-Sison).

D.Penatalaksanaan atau Pengobatan
a. Kuretase isap (suction curettage)
Apabila pasien menginginkan keturunan di kemudian hari, penanganan yang dipilih
adalah evakuasi jaringan mola dengan kuretase isap. Dua sampai empat unit darah harus tersedia
karena evakuasi dapat disertai dengan kehilangan darah yang banyak.setelah evakuasi awal,
kontraksi uterus dirangsang dengan oksitosin intravena untuk mengurangi kehilangan
darah.jaringan-jaringan sisa dibersikan dengan kuretase tajam.spesimennya dikirim secara
terpisah ke laboratorium patologi.
b. Histerektomi abdominal
Pada mola ini merupakan suatu alternatif lain bagi pasien yang tidak lagi menginginkan
kehamilan di kemudian hari.Histerektomi menyingkirkan kemungkinan berfungsinya sel-sel
trofoblastik yang tertinggal di dalam uterus setelah kuretase isap dan mengurai resiko penyakit
trofoblastik residual sampai 3-5%.keputusan mengenai salpingo-ooforektomi adalah
tersendiri.setelah pengeluaran mola dan pengurangan stimulas chorionic gonadotropin,kista
teka-lutein ovarium mengalami regresi secara spontan. Pengangkatan dengan pembedahan hanya
diperlukan bila ada kaitan dengan torsi atau perdarahan.
c. Program lanjut
Setelah evakuasi suatu kehamilan mola pasien diamati dengan seksama terhadap serangkaian
titer chorionic gonadotropin (HCG),
menggunakan radioimmunoassay untuk submit beta, setiap satu atau dua minggu sampai
negative. Hilangnya HCG secara sempurna diperkirakan terjadi dalam 9-15 minggu setelah
pengosongan uterus. Pasien disarankan untuk menghindari kehamilan sampai titer chorionic
gonadotropin negative selama satu tahun. Biasanya diberikan kontrasepsi oral estrogen-
progestin. Pelvis diperiksa secara berkala untuk menilai ukuran uterus, adneksa untuk kista teka-
lutein, dan traktus genitalis bagian bawah untuk metastase.
Apabila 2 titer chorionic gonadotropin yang berurutan stabil (plateu) atau meningkat atau
apabila tampak adanya metastase, pasien harus dievaluasi terhadap keganasan neoplasia

tropoblastik gestasional dan kemoterapi. Hamper 15-20% pasien dengan Mola Hidatidosa
berkembang gejala keganasan ssetetal kuretase isap. Dari kelompok ini hamper 80% menderita
penyakit trofoblastik non metastatic sedangkan yang 20% menderita metastase keluar batas
uterus, paling sering ke paru-paru atau vagina. Selain titer chorionic gonadotropin yang
persisten atau meningkat, gejala keganasan neoplsia trofoblastik gestasional meliputi perdarahan
pervaginam yang persisten, pendarahan intra abdominal dan lesi perdarahan di paru-paru, hepar,
otak, atau ogan-organ lainnya.
E. Prognosis Mola Hidatidosa
Hampir 20% mola hidatidosa komplet berlanjut menjadi keganasan, sedangkan mola
hidatidosa parsial jarang. Mola yang terjadi berulang disertai tirotoksikosis atau kista lutein
memiliki kemungkinan menjadi ganas lebih tinggi.
Prognosis Kematian pada mola hidatidosa disebabkan perdarahan, infeksi, payah jantung
atau tirotoksikosis. Sebagian dari pasien mola akan segera sehat kembali setelah jaringannya
dikeluarkan, tetapi ada sekelompok perempuan yang kemudian menderita degenerasi keganasan
menjadi koriokarsinoma.
Bila tindakan penanganan dan pengobatan telah dilakukan secara cepat dan tepat, maka
ibu dapat berpeluang untuk hamil kembali. Kontrol rutin tetap harus dijalani sesuai ketentuan
prosedur dari dokter. Bila pemeriksaan kadar HCG dalam darah sampai tiga kali berturut turut
negatif, ibu boleh pulng dengan diberi konseling penggunaan alat kontrasepsi untuk menunda
kehamilan.Alat kontrasepsi pilhan bisa pil, atau IUD.

I. Konsep Dasar Penyakit
A. Pengertian
Menurut beberapa ahli pengertian mola hidatidosa adalah sebagai berikut :
• Mola hidatidosa adalah chorionic villi (jonjotan/gantungan) yang tumbuh berganda berupa
gelembung-gelembung kecil yang mengandung banyak cairan sehingga menyerupai buah anggur
atau mata ikan. Karena itu disebut juga hamil anggur atau mata ikan. (Mochtar, Rustam, dkk,
1998 : 23).
• Mola hidatidosa adalah kehamilan abnormal, dengan ciri-ciri stoma villus korialis langka,
vaskularisasi dan edematus. Janin biasanya meninggal akan tetapi villus-villus yang membesar
dan edematus itu hidup dan tumbuh terus, gambaran yang diberikan adalah sebagai segugus buah
anggur. (Wiknjosastro, Hanifa, dkk, 2002 : 339).
• Mola hidatidosa adalah perubahan abnormal dari villi korionik menjadi sejumlah kista yang
menyerupai anggur yang dipenuhi dengan cairan. Embrio mati dan mola tumbuh dengan cepat,
membesarnya uterus dan menghasilkan sejumlah besar human chorionic gonadotropin (hCG)
(Hamilton, C. Mary, 1995 : 104).
• Mola hidatidosa adalah kehamilan abnormal di mana hampir seluruh villi kariolisnya mengalami
perubahan hidrofobik. (Mansjoer, Arif, dkk, 2001 : 265).
• Mola hidatidosa adalah kelainan villi chorialis yang terdiri dari berbagai tingkat proliferasi
tropoblast dan edema stroma villi. (Jack A. Pritchard, dkk, 1991 : 514).
• Mola hidatidosa adalah pembengkakan kistik, hidropik, daripada villi choriales, sdisertai
proliperasi hiperplastik dan anaplastik epitel chorion. Tidak terbentuk fetus ( Soekojo, Saleh,
1973 : 325).
• Mola hidatidosa adalah perubahan abnormal dari villi korionik menjadi sejumlah kista yang
menyerupai anggur yang dipenuhi dengan cairan. Embrio mati dan mola tumbuh dengan cepat,
membesarnya uterus dan menghasilkan sejumlah besar human chorionic gonadotropin (hCG)
(Hamilton, C. Mary, 1995 : 104).
Berdasarkan beberapa pengertian diatas yang dimaksud dengan mola hidatidosa adalah
kehamilan abnormal dimana hampir seluruh villi kariolisnya mengalami perubahan hidrofobik
yang menyerupai anggur yang dipenuhi dengan cairan dengan ciri-ciri stoma villus korialis

langka, vaskularisasi dan edematous. Embrio mati dan mola tumbuh dengan cepat, membesarnya
uterus dan menghasilkan sejumlah besar human chorionic gonadotropin (hCG).
B. Penyebab
Penyebab mola hidatidosa belum diketahui secara pasti, namun faktor penyebabnya
adalah
• Faktor ovum : ovum memang sudah patologik sehingga mati , tetapi terlambat dikeluarkan.
• Imunoselektif dari tropoblast
• Keadaan sosio-ekonomi yang rendah
• Kekurangan protein dan asam folat, infeksi virus dan faktor kromosom yang belum jelas
• Kekurangan gizi pada ibu hamil.
• Kelainan rahim.
• Wanita dengan usia dibawah 20 tahun atau diatas 40 tahun.
C. Tanda dan Gejala
Kecurigaaan biasanya terjadi pada minggu ke 14 – 16, dimana kita dapat melihat adanya
tanda-tanda seperti dibawah ini :
• Ukuran rahim lebih besar dari kehamilan biasa
• Pembesaran rahim yang terkadang diikuti perdarahan
• Bercak berwarna merah darah beserta keluarnya materi seperti anggur pada pakaian dalam.
Adapun gejala dari mola hidatidosa adalah :
• Mual dan muntah yang parah yang menyebabkan 10% pasien masuk RS.
• Pembesaran rahim yang tidak sesuai dengan usia kehamilan (lebih besar).
• Gejala – gejala hipertitoidisme seperti intoleransi panas, gugup, penurunan berat badan yang
tidak dapat dijelaskan, tangan gemetar dan berkeringat, kulit lembab.
• Gejala – gejala preeklampsi seperti pembengkakan pada kaki dan tungkai, peningkatan tekanan
darah, proteinuria.
D. Patofisiologi
E. Klasifikasi

Klasifikasi mola hidatidosa berdasarkan ada atau tidaknya janin yaitu :
• Mola Hidatidosa Komplit (Klasik)
Villi korion berubah menjadi massa vesikel dengan ukuran bervariasi dari sulit terlihat sehingga
diameter beberapa centimeter. Histologinya memiliki karakteristik yaitu :
• Tidak ada pembuluh pada vili yang membengkak
• Prolifersi dari epitel trofoblas dengan bermacam-macam ukuran
• Tidak adanya janin atau amnion
• Mola Hidatidosa Inkomplit (Parsial)
Masih tampak gelembung yang disertai janin atau bagian dari janin. Umumnya janin masih
hidup dalam bulan pertama. Tetapi ada juga yang hidup sampai aterm. Pada pemeriksaan
histopatologik tampak di beberapa tempat villi yang edema dengan sel trofoblas yang tidak
begitu berproliferasi, sedangkan tempat lain masih banyak yang normal.
F. Manifestasi Klinik
Gambaran klinik yang biasanya timbul pada klien dengan ”mola hidatidosa” adalah :
• Amenore dan tanda-tanda kehamilan
• Perdarahan pervaginam berulang. Darah cenderung berwarna coklat. Pada keadaan lanjut
kadang keluar gelembung mola.
• Pembesaran uterus lebih besar dari usia kehamilan.
• Tidak terabanya bagian janin pada palpasi dan tidak terdengarnya BJJ sekalipun uterus sudah
membesar setinggi pusat atau lebih. Preeklampsia atau eklampsia yang terjadi sebelum
kehamilan 24 minggu.
• Pemeriksaan Penunjang
• Pemeriksaan Fisik
• Mola lengkap (Complete mole)

• Tanda klasik: pembesaran uterus lebih besar dari usia kehamilan yang diharapkan, atau dengan
kata lain, ukuran (uterus) inkonsisten dengan usia kehamilan.
Pembesaran yang tidak diharapkan ini disebabkan oleh pertumbuhan trofoblas yang berlebihan
(excessive trophoblastic growth) dan darah yang tertahan (retained blood)
• Preeclampsia (Preeklamsia)
Sekitar 27% pasien mola lengkap disertai toksemia, yang
ditandai dengan:
• hipertensi (tekanan darah>140/90 mmHg)
• proteinuria (>300 mg/hari)
• edema dengan hyperreflexia, kejang (convulsion) jarang terjadi.
• Kista teka lutein (Theca lutein cysts)
Kista ini merupakan kista ovarium yang berdiameter lebih dari 6 cm dan menyertai pembesaran
ovarium. Karena meningkatnya ukuran ovarium, dapat berisiko terjadi puntiran (torsion). Kista
ini tidak terdeteksi dengan palpasi bimanual namun teridentifikasi dengan USG
(ultrasonography). Selain itu, kista ini berkembang sebagai respon (tanggapan) atas tingginya
kadar beta-HCG, dan mengecil spontan setelah mola dievakuasi (diangkat).
• Mola parsial (Partial mole)
• Pembesaran uterus dan preeclampsia dilaporkan terjadi hanya pada 3% pasien.
• Jarang disertai kista teka lutein, hiperemesis, dan hipertiroidisme.
Kembar (Twinning).
• Kembar dengan mola lengkap dan janin (fetus) dengan plasenta normal telah dilaporkan. Kasus
bayi sehat pada keadaan seperti ini telah dilaporkan pula.
• Wanita dengan coexistent molar dan kehamilan (gestation) normal berisiko tinggi untuk
berkembang menjadi persistent disease dan metastasis. Tindakan mengakhiri kehamilan
(termination of pregnancy) merupakan pilihan yang direkomendasikan.

• Kehamilan dapat dilanjutkan selama status maternal stabil, tanpa perdarahan (hemorrhage),
thyrotoxicosis, atau hipertensi berat. Pasien haruslah diberitahu tentang tingginya risiko
morbiditas maternal (kematian ibu) ari komplikasi yang mungkin terjadi.
• Diagnosis genetika prental melalui sampel chorionic villus atau amniocentesis
direkomendasikan untuk mengevaluasi karyotype janin (fetus).
• Pemeriksaan Laboratorium
• Quantitative beta-HCG
Kadar HCG lebih dari 100,000 mIU/mL mengindikasikan pertumbuhan trofoblas yang
berlebihan (exuberant trophoblastic growth) dan dugaan adanya kehamilan mola haruslah
disingkirkan. Kadar HCG pada kehamilan mola biasanya normal.
• Hitung darah lengkap dengan trombosit (complete blood cell count with platelets)
Anemia merupakan komplikasi medis yang umum terjadi, sebagai perkembangan (development)
dari proses koagulopati.
• Fungsi pembekuan (clotting function)
Tes ini dilakukan untuk menyingkirkan dugaan adanya komplikasi akibat proses perkembangan
koagulopati.
• Tes fungsi hati (Liver function test)
• Blood urea nitrogen (BUN) dan kreatinin
• Thyroxin
Meskipun wanita dengan kehamilan mola secara klinis biasanya euthyroid, namun kadar plasma
thyroxin biasanya naik di atas nilai normal wanita dengan kehamilan normal. Di samping itu,
gejala hyperthyroidism dapat terjadi.
• Serum inhibin A dan activin A
Serum inhibin A dan activin A menjadi 7-10 kali lipat lebih tinggi pada kehamilan mola
dibandingkan dengan kehamilan normal pada usia kehamilan (gestational) yang sama.

• Komplikasi
Komplikasi yang terjadi pada pasien dengan gangguan mola hidatidosa adalah :
• Perforasi uterus saat melakukan tindakan kuretase (suction curettage) terkadang terjadi karena
uterus luas dan lembek (boggy). Jika terjadi perforasi, harus segera diambil tindakan dengan
bantuan laparoskop.
• Perdarahan (hemorrhage) merupakan komplikasi yang sering terjadi saat pengangkatan
(evacuation) mola. Oleh karena itu, oksitosin intravena harus diberikan sebelum evakuasi mola.
Methergine dan atau Hemabate juga harus tersedia. Selain itu, darah yang sesuai dan cocok
dengan pasien juga harus tersedia.
• Penyakit trofoblas ganas (malignant trophoblastic disease) berkembang pada 20% kehamilan
mola. Oleh karena itu, quantitative HCG sebaiknya dimonitor terus-menerus selama satu tahun
setelah evakuasi (postevacuation) mola sampai hasilnya negatif.
• Pembebasan faktor-faktor pembekuan darah oleh jaringan mola memiliki aktivitas fibrinolisis.
Oleh karena itu, semua pasien harus diskrining untuk disseminated intravascular coagulopathy
(DIC).
• Emboli trofoblas dipercaya menyebabkan acute respiratory insufficiency. Faktor risiko terbesar
adalah ukuran uterus yang lebih besar dibandingkan usia kehamilan (gestational age) 16 minggu.
Kondisi ini dapat menyebabkan kematian.
• PenatalaksanaanPenatalaksanaan yang biasa dilakukan pada mola hidatidosa adalah :
• Diagnosis dini akan menguntungkan prognosis
• Pemeriksaan USG sangat membantu diagnosis. Pada fasilitas kesehatan di mana sumber daya
sangat terbatas, dapat dilakukan : Evaluasi klinik dengan fokus pada : Riwayat haid terakhir dan
kehamilan Perdarahan tidak teratur atau spotting, pembesaran abnormal uterus, pelunakan
serviks dan korpus uteri. Kajian uji kehamilan dengan pengenceran urin. Pastikan tidak ada janin
(Ballottement) atau DJJ sebelum upaya diagnosis dengan perasat Hanifa Wiknjosastro atau
Acosta Sisson
• Lakukan pengosongan jaringan mola dengan segera

• Antisipasi komplikasi (krisis tiroid, perdarahan hebat atau perforasi uterus)
• Lakukan pengamatan lanjut hingga minimal 1 tahun. Selain dari penanganan di atas, masih
terdapat beberapa penanganan khusus yang dilakukan pada pasien dengan mola hidatidosa,
yaitu : Segera lakukan evakuasi jaringan mola dan sementara proses evakuasi berlangsung
berikan infus 10 IU oksitosin dalam 500 ml NaCl atau RL dengan kecepatan 40-60 tetes per
menit (sebagai tindakan preventif terhadap perdarahan hebat dan efektifitas kontraksi terhadap
pengosongan uterus secara tepat). Pengosongan dengan Aspirasi Vakum lebih aman dari
kuretase tajam. Bila sumber vakum adalah tabung manual, siapkan peralatan AVM minimal 3 set
agar dapat digunakan secara bergantian hingga pengosongan kavum uteri selesai. Kenali dan
tangani komplikasi seperti tirotoksikasi atau krisis tiroid baik sebelum, selama dan setelah
prosedur evakuasi. Anemia sedang cukup diberikan Sulfas Ferosus 600 mg/hari, untuk anemia
berat lakukan transfusi. Kadar hCG diatas 100.000 IU/L praevakuasi menunjukkan masih
terdapat trofoblast aktif (diluar uterus atau invasif), berikan kemoterapi MTX dan pantau beta-
hCG serta besar uterus secara klinis dan USG tiap 2 minggu.