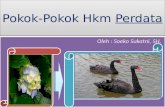hukumcara perdata
description
Transcript of hukumcara perdata

Nama : RiswandiNPM : 110110120167
HUKUM ACARA PERDATA
1. Peradilan khusus baru
Pada tahun 1964, dengan UU No. 19 Tahun 1964 – seperti sudah dikemukakan di atas – dibedakan adanya tiga macam peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kedua bentuk Pengadilan Ekonomi dan Pengadilan Land-reform tersebut di atas termasuk ke dalam pengertian Peradilan Umum, sedangkan yang dimaksud dengan Peradilan Khusus adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Militer. Sementara itu, yang dimaksud dengan Peradilan Tata Usaha Negara adalah peradilan sebagaimana disebut dalam Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 sebagai peradilan administratif. Di dalamnya tercakup juga pengertian peradilan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU No. 18 Tahu 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian (LNRI 1961 No. 263; TLN No.2312). Peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara ini baru diperlakukan sebagai lingkungan peradilan sendiri yang setara dengan peradilan umum dengan dicantumkannya ketentuan mengenai keempat lingkungan peradilan itu dalam UU No. 14 Tahun 1970. Dengan demikian, pengertian pengadilan khusus ditiadakan dan diganti dengan pengertian lingkungan peradilan.
Namun, sebelum dibentuknya UU No. 14 Tahun 1970 ini, di masa awal Orde Baru, meskipun bentuk-bentuk pengadilan khusus, seperti Pengadilan Ekonomi dan Pengadilan Land-Reform tersebut di atas sudah tidak ada lagi, tetapi ketika itu muncul kebutuhan yang dipandang mendesak untuk membentuk pengadilan khusus untuk mengadili eks anggota Partai Komunis Indonesia beserta
antek-anteknya. Untuk memenuhi kebutuhan pasca G.30.S./PKI, maka dibentuk lah pengadilan yang bersifat istimewa berdasarkan prinsip-prinsip hukum militer yang bersifat sementara. Pengadilan khusus ini disebut Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub). Ketika itu, kedudukan Mahmilub ini sangat penting dan kinerjanya sangat efektif dan progresif dalam mengadili dan menghukum orang- orang yang dipandang terkait dengan PKI dan peristiwa G.30.S/PKI. Perkembangan demikian ini terus berlangsung sampai kemudian dilakukan konsolidasi dan penataan struktural terhadap sistem peradilan nasional pada tahun 1970 dengan dibentuknya UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok- Pokok Kekuasaan Kehakiman. UU ini memperkenalkan pengelompokan peradilan ke dalam 4 lingkungan peradilan, yaitu:
1. Peradilan umum 2. Peradilan agama3. Peradilan tata usaha negara4. Peradilan militer
Karena besarnya pengaruh sistem peradilan militer melalui Mahkamah Militer Luar

Biasa (Mahmilub) mulai tahun 1965, struktur peradilan militer itu dimuat dalam Undang-Undang Pokok- Pokok Kekuasaan Kehakiman itu sebagai salah satu lingkungan peradilan yang tersendiri, di samping peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata-usaha negara, yang masing-masing dapat dikatakan mempunyai latar belakarang ide dan sejarahnya sendiri-sendiri. Seharusnya, peradilan militer tidak perlu dimasukkan ke dalam rezim hukum peradilan biasa, karena fungsinya terkait dengan hukum keadaan darurat, bukan hukum dalam keadaan normal. Dalam keadaan normal, peradilan militer itu seharusnya hanya dikaitkan dengan fungsi peradilan disiplin internal prajurit dan perwira militer. Pengadilan Militer dapat berfungsi, baik sebagai peradilan sipil maupun sebagai peradilan militer secara bersama-sama, hanya dalam kondisi negara dalam keadaan darurat perang atau keadaan darurat militer.
Karena itu, keberadaan pengadilan militer seharusnya hanya tidak diperlakukan sebagai lingkungan peradilan yang tersendiri, melainkan cukuplah dipandang sebagai salah satu bentuk pengadilan khusus, yaitu bersifat internal militer ketika kondisi negara berada dalam keadaan normal, dan bersifat eksternal dengan kemungkinan menjalankan fungsi peradilan sipil manakala fungsi-fungsi peradilan sipil tidak dapat menjalankan tugas konstitusionalnya berhubungan kondisi negara berada dalam keadaan darurat perang atau darurat militer. Dengan demikian, keadilan tidak malah dicampur-adukkan antara kondisi negara dalam keadaan normal dan keadaan tidak normal. “Normale recht voor normale tijd, en abnormale recht voor abnormale tijd” (hukum yang normal untuk keadaan norma,
dan hukum yang tidak normal untuk keadaan tidak normal)5. Inilah pentingnya kita membedakan antara pengertian Hukum Tata Negara Biasa dan Hukum Tata Negara Darurat.
Pengadilan khusus pasca Reformasi
Ide pembentukan peradilan khusus terutama sangat berkembang di masa setelah reformasi, terutama untuk maksud memenuhi tuntutan perkembangan akan keadilan yang semakin kompleks dalam masyarakat. Pada akhir masa Orde Baru, dibentuk satu pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Anak berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997. Setelah reformasi, desentralisasi pemerintahan dan diversifikasi fungsi-fungsi kekuasaan negara berkembang luas bersamaan dengan gerakan liberalisasi dan demokratisasi di segala bidang kehidupan. Karena itu, lembaga peradilan yang bersifat khusus semakin banyak didirikan oleh Pemerintah. Pada tahun 1998, dengan Perpu No. 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998, kita mendirikan Pengadilan Niaga yang pertama kali. Selanjutnya, pada tahun 2000 dan tahun 2002, kita membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan UU No. 26 Tahun 2000, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) dengan UU No. 30 Tahun 2002.
Selain itu, kita juga membentuk Pengadilan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004, dan Pengadilan Perikanan berdasarkan UU No. 31 Tahun 2004, dan banyak lagi lainnya. Sampai sekarang, pengadilan khusus yang ada sudah tercatat lebih dari 10 macam, yaitu:

1. Pengadilan anak1 (bidang hukum pidana)2. Pengadilan Niaga2 (bidang hukum perdata)3. Pengadilan HAM3 (bidang hukum pidana)4. Pengadilan TIPIKOR4 (bidang hukum pidana)5. Pengadilan Hubungan Industrial5 (bidang hukum perdata)
6. Pengadilan Perikanan6 (bidang hukum pidana);7. Pengadilan Pajak7 (bidang hukum TUN);8. Mahkamah Pelayaran (bidang hukum perdata);9. Mahkamah Syar’iyah di Aceh8 (bidang hukum agama Islam);10. Pengadilan Adat di Papua 9(eksekusi putusannya terkait dengan peradilan umum); dan11. Pengadilan Tilang.10
Lembaga-lembaga Semi atau Quasi Peradilan
Di samping lembaga Pengadilan Khusus yang dalam undang-undang secara tegas dan resmi disebut sebagai pengadilan, dewasa ini juga banyak tumbuh dan berkembang adanya lembaga- lembaga yang meskipun tidak disebut eksplisit sebagai pengadilan, tetapi memiliki kewenangan dan makanisme kerja yang juga bersifat mengadili. Berdasarkan ketentuan undang-undang, lembaga- lembaga demikian ini diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus sesuatu perselisihan ataupun perkara pelanggaran hukum, dan bahkan perkara pelanggaran etika tertentu dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat (final and binding) sebagaimana putusan pengadilan yang bersifat “inkracht” pada umumnya. Semua ini dimaksudkan untuk memberikan keadilan bagi para pihak yang dirugikan oleh sesuatu sistem pengambilan keputusan yang mengatas-namakan kekuasaan negara.
Karena itu, dapat dikatakan bahwa lembaga-lembaga yang bersifat ‘mengadili’ tetapi tidak disebut sebagai pengadilan itu merupakan bentuk quasi pengadilan atau semi pengadilan. Beberapa di antaranya berbentuk komisi-komisi negara, tetapi ada pula yang menggunakan istilah badan atau pun dewan. Lembaga-lembaga ini, di samping bersifat mengadili, seringkali juga memiliki fungsi- fungsi yang bersifat campuran dengan fungsi regulasi dan/ataupun fungsi administrasi. Fungsi regulasi dapat dikaitkan dengan fungsi legislatif menurut doktrin ‘trias-politica Mostesquieu’, sedangkan fungsi administrasi identik dengan fungsi eksekutif. Karena itu, komisi-komisi negara atau lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan mengadili ini dapat dikatakan merupakan lembaga yang memiliki fungsi campuran. Sebagai contoh dapat dikemukakan beberapa di antaranya sebagai berikut:
1 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (LNRI 1997 No.3, TLNRI No.3668).2 UU No. 4 Tahun 1999 (LNRI 1999 No. 135 dan TLN No. 3778) dan Perpu No. 1 Tahun 1998.3 UU No. 26 Tahun 2000 (LNRI 2000 No.208, TLN No. 4026).4 UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI 2000 no. 137, TLN No. 4250).5 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LNRI 2004 No. 6, TLN No. 4356).6 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (LNRI 2004 No. 11, TLN No. 4433).7 UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (LNRI 2002 No. 27, TLN No. 4189).8 Pertama kali dibentuk dengan Keputusan Presiden No.11 Tahun 2002.9 Lihat UU tentang Otonomi Khusus Papua.10 Lihat UU tentang Kepolisian Republik Indonesia.

1) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)11
2) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)12
3) Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Komisi Informasi Daerah (KID)13
4) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)14
5) Ombudsman Republik Indonesia (ORI)15
6) Dan lain-lain.
SUMBER: Tulisan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. yang berjudul “Peradilan khusus”
2. Kompetensi Pengadilan
Kompetensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu). Kompetensi dari suatu pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara berkaitan dengan jenis dan tingkatan pengadilan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan jenis dan lingkungan pengadilan dibedakan atas Pengadilan Umum, Pengadilan Militer, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara (Pengadilan Administrasi). Sedangkan berdasarkan tingkatannya pengadilan terdiri atas Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi (Banding), dan Mahkamah Agung (Pengadilan Tingkat Kasasi).
Dengan demikian jumlah pengadilan tingkat pertama ditentukan oleh jumlah pemerintah daerah tingkat II (Kabupaten/Kotamadya) yang ada, jumlah pengadian tingkat tinggi (banding) sebanyak jumlah pemerintahan tingkat I (provinsi),
Sedangkan Mahkamah Agung (kasasi) hanya ada di ibukota Negara sebagai puncak dari semua lingkungan peradilan yang ada.
Ada beberapa cara untuk mengetahui kompetensi dari suatu pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara : pertama, dapat dilihat dari pokok sengketanya[3]. [3]. kedua dengan melakukan pembedaan atas atribusi dan delegasi[4]. [4]. ketiga dengan melakukan pembedaan atas kompetensi absolut dan kompetensi relatif.
11 Lembaga ini dibentuk berdasarkan UU No. 9 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persiangan Usaha tidak Sehat.12 Komisi Penyiaran Indonesia dibentuk berdasarkan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.13 Komisi ini dibentuk berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.14 Bawaslu dibentuk berdasarkan UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.15 Semula lembaga ini bernama Komisi Ombudsman Nasional (KON) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 44 tahun 2000. Pada tahun 2008, kedudukan lembaga ini ditingkatkan dan namanya diubah menjadi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) berdasarkan UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.[3].
[4].

Dapat dilihat dari pokok sengketanya, apabila pokok sengketanya terletak dalam lapangan hukum privat, maka sudah tentu yang berkompetensi adalah hakim biasa (hakim pengadilan umum). Apabila pokok sengketanya terletak dalam lapangan hukum publik, maka sudah tentu yang berkompetensi adalah administrasi negara yang berkuasa (hakim PTUN).
Menurut Sjarah Basah pembagian kompetensi atas atribusi dan delegasi dapat dijelaskan melalui bagan nerikut:
a. Atribusi berkaitan dengan pemberian wewenang yang bersifat bulat (absolut) mengenai materinya, yang dapat dibedakan:
1) Secara horizontal, yaitu wewenang yang bersifat bulat dan melekat dari suatu jenis pengadilan lainnya, yang mempunyai kedudukan sederajat/setingkat. Contoh; Pengadilan Administrasi terhadap Pengadilan Negeri (Umum), Pengadilan Agama atau Pengadilan Militer.
2) Secara vertikal, yaitu wewenang yang bersifat bulat dan melekat dari suatu jenis pengadilan terhadap jenis pengadilan lainnya, yang secara berjenjang atau hirarkis mempunyai kedudukan lebih tinggi. Contoh; Pengadilan Negeri (Umum) terhadap Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
b. Distribusi berkaitan dengan pemberian wewenang, yang bersifat terinci (relatif) di antara badan-badan yang sejenis mengenai wilayah hukum. Contoh; Pengadilan Negeri Bandung dengan Pengadilan Negeri Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis.
Pembagian yang lain adalah pembagian atas kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif.
a. Kompetensi Absolut
Menyangkut kewenangan badan peradilan apa untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara; sebagaimana diketahui berdasarkan pasal 10 UU 35/1999 kita mengenal 4 (empat) lingkungan peradilan, yakni; peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
1) Kompetensi Absolut Dari Peradilan Umum adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana yang dilakukan oleh orang-orang sipil dan perkara perdata, kecuali suatu peraturan perundang-undangan menentukan lain (Pasal 50 UU 2/1999).
2) Kompetensi Absolut Dari Peradilan Agama adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara-perkara orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, waqaf, dan shadaqah (Pasal 49 UU 50/2009).
3) Kompetensi Absolut Dari Peradilan Militer adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana yang dilakuka oleh anggota militer (baik dari angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara , dan kepolisian).
4) Kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara seseorang atau

badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian (Pasal 1 ayat 4 UU 09/2004 PTUN) dan tidak dikeluarkannya suatu keputusan yang dimohonkan yang dimohonkan seseorang sampai batas waktu yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan, sedangkan hal itu telah merupakan kewajiban badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan (Pasal 3 UU 09/2004 PTUN).
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa istilah atribusi dari Sjarah Basah itu sama dengan kompetensi absolut dan untuk istilah delegasi adalah sama dengan kompetensi relatf.
. Contoh : Suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anggota ABRI maka pengadilan yang berwenang untuk mengadili adalah Pengadilan Militer
Kewenangan Relatif Pengadilan
Kewenangan relatif pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayahnya, yaitu untuk menjawab pertanyaan “Pengadilan Negeri wilayah mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara?”. Dalam hukum acara perdata, menurut pasal 118 ayat (1) HIR, yang berwenang mengadili suatu perkara perdata adalah Pengadilan Negeri (PN) yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat (actor sequitur forum rei). Mengajukan gugatan pada pengadilan diluar wilayah hukum tempat tinggal tergugat, tidak dibenarkan.
Persoalannya adalah, bagaimana jika seorang tergugat memiliki beberapa tempat tinggal yang jelas dan resmi. Dalam hal ini, penggugat dapat mengajukan gugatan ke salah satu PN tempat tinggal tergugat tersebut. Misalnya, seorang tergugat dalam KTP-nya tercatat tinggal di Tangerang dan memiliki ruko di sana, sementara faktanya ia juga tinggal di Bandung. Dalam hal demikian, gugatan dapat diajukan baik pada PN di wilayah hukum Tangerang maupun Bandung. Dengan demikian, titik pangkal menentukan PN mana yang berwenang mengadili perkara adalah tempat tinggal tergugat dan bukannya tempat kejadian perkara (locus delicti) seperti dalam hukum acara pidana.
Dalam hal suatu perkara memiliki beberapa orang tergugat, dan setiap tergugat tidak tinggal dalam suatu wilayah hukum, maka penggugat dapat mengajukan gugatan ke PN yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal salah seorang tergugat. Kepada penggugat diberikan hak opsi, asalkan tergugat terdiri dari beberapa orang dan masing-masing tinggal di daerah hukum PN yang berbeda.
Jika tergugat terdiri lebih dari satu orang, dimana tergugat yang satu berkedudukan sebagai debitur pokok (debitur principal) sedangkan tergugat lain sebagai penjamin (guarantor), maka kewenang relatif PN yang mengadili perkara tersebut jatuh pada PN yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal debitur pokok tersebut.
Opsi lainnya adalah gugatan diajukan kepada PN yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, yaitu dengan patokan apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui. Agar tidak dapat dimanipulasi oleh penggugat, tidak diketahuinya tempat tinggal tergugat itu

perlu mendapat surat keterangan dari pejabat yang bersangkutan yang menyatakan bahwa tempat tinggal tergugat tidak diketahui. Misalnya, surat keterangan dari kepala desa.
Jika obyek gugatan mengenai benda tidak bergerak (benda tetap), misalnya tanah, maka gugatan diajukan kepada PN yang daerah hukumnya meliputi benda tidak bergerak itu berada. Jika keberadaan benda tidak bergerak itu meliputi beberapa wilayah hukum, maka gugatan diajukan ke salah satu PN atas pilihan penggugat. Namun jika perkara itu merupakan perkara tuntutan ganti rugi berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) pasal 1365 KUHPerdata yang sumbernya berasal dari obyek benda tidak bergerak, maka tetap berlaku asas actor sequtur forum rei (benda tidak bergerak itu merupakan “sumber perkara” dan bukan “obyek perkara”). Misalnya, tuntutan ganti rugi atas pembaran lahan perkebunan.
Dalam perjanjian, terkadang para pihak menentukan suatu PN tertentu yang berkompetensi memeriksa dan mengadili perkara mereka. Hal ini, berdasarkan asas kebebasan berkontrak, bisa saja dimasukan sebagai klausul perjanjian, namun jika terjadi sengketa, penggugat memiliki kebebasan untuk memilih, apakah PN berdasarkan klausul yang ditunjuk dalam perjanjian itu atau berdasarkan asas actor sequtur forum rei. Jadi, domisili pilihan dalam suatu perjanjian tidak secara mutlak menyingkirkan asas actor sequitur forum rei, dan tergugat tidak dapat melakukan eksepsti terhadap tindakan tersebut.
CONTOH :
Suatu tindak pidana yang terjadi di Cimahi maka yang berwenang untuk mengadili adalah Pengadilan Negeri Bale Bandung.
2. Pihak-pihak dalam perkara
Penggugat.
Yakni, orang yang merasa hak-hak hukumnya dilanggar, dan jika terdiri dari beberapa pihak yang merasa sama-sama dilanggar haknya, dapat juga mengajukan gugatan bersama-sama sehingga disebut juga Para Penggugat.
Tergugat
Yakni orang atau para pihak yang disangkakan telah melanggar hak-hak hukum penggugat, jika hanya ada satu tergugat cukup disebut tergugat, namun jika ada beberapa maka masing-masing ditulis Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dst dengan didasari oleh derajat hubugngan masing-masing dalam menuliskan siapa Tergugat I, siapa Tergugat II, dst. Dan secara bersama-sama keseluruhannya disebut Para Tergugat.

Turut Tergugat
Yakni pihak lain yang turut digugat dengan tujuan untuk menjadikan gugatan tersebut terlihat lengkap. Misalnya dalam perkara perbuatan wanprestasi, maka turut tergugat ini bukanlah pihak yang melakukan wanprestasi tersebut, namun dia terkait dalam kronologi kejadian perkara misalnya. Sehingga dalam putusan hakim nantinya, jika gugatan penggugat dikabulkan maka turut tergugat tidak ikut untuk menjalankan hukuman namun hanya tunduk dan patuh terhadap putussan tersebut, dan perbedaan dalam menjalankan putusan ini juga yang menjadi perbedaan mendasar antara Tergugat dengan Turut Tergugat.
Penggugat Intervensi / Tergugat Intervensi
Jika dalam perkara yang sedang berlangsung, ada pihak ketiga yang merasa memiliki kepentingan terhadap perkara tersebut, maka dia dapat melibatkan dirinya atau dilibatkan oleh slah satu pihak dalam perkara tersebut. Inilah yang biasa disebut dengan Intervensi. Dalam melakukan intervensi, pihak ketiga dapat melakukannya sebagai Penggugat Intervensi atau Tergugat Intervensi. Pengikut sertaan pihak ketiga dalam proses berperkara ini biasanya dalam bentuk Voeging, Intervensi/Tussenkomst, dan Vrijwaring. Ketiganya ini tidak diatur di dalam HIR maupun RBG, namun aturannya terdapat di dalam Rv16. Dan beberapa yurisprudensi.
1. Voeging (menyertai)
Pasal 279 Rv berbunyi “Barangsiapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan”. Di dalam Voeging pihak yang ikut serta akan menyertakan diri kepada salah satu pihak, apakah itu pihak tergugat ataupun pihak penggugat. Namun dalam praktik biasanya menyertakan diri untuk bergabung dengan pihak tergugat disebabkan adanya kepentingan yang sama dengan pihak tergugat sehingga ikut campur untuk mempertahankan kepentingannya itu. Prosesnya di pengadilan jika ada pihak yang mengajukan Voeging maka hakim akan memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak yang sedang bersengketa untuk memberikan tanggapan, kemudian akan diputuskan oleh hakim dalam putusan sela jika permohonan Voeging tersebut dikabulkan.
2. Intervensi / Tussenkomst
Yurisprudensi MA No. 731 K/Sip/1975,17 menyatakan “Intervensi (i.c. tussenkomst) adalah fihak ke-3 yang tadinya berdiri di luar acara sengketa ini, kemudian masuk dalam proses untuk membela kepentingannya sendiri”. Dalam hal ini, pihak Intervensi merasa
16 Meskipun Rv telah dinyatakan tidak berlaku lagi dengan undang-undang Darurat No. 1/1951, namun dalam praktiknya seringkali aturan ini masih diterapkan guna memperoleh referensi dan mengisi kekosongan hukum.17 Tanggal keputusan yakni 16 Desember 1976.

kepentingannya atau barang miliknya sedang disengketakan antara penggugat maupun tergugat sehingga dia masuk untuk mengintervensi. Dalam prosesnya hakim akan memutuskan dalam putusan sela apakah akan menerima intervensi tersebut atau tidak, jika menerima maka aka nada dua perkara yang akan diproses bersama-sama, yakni gugatan asal dan gugatan intervensi.
3. Vrijwaring (ditarik sebagai penjamin)
Pasal 70 Rv berbunyi “jika seorang tergugat berpendapat ada alasan untuk memanggil seseorang untuk menanggungnya dan pemanggilan tidak dilakukan sebelum hari siding pemeriksaan perkaranya, maka ia pada hari yang ditentukan untuk mengadakan bantahan harus mengajukan kesimpulan disertai alasan-alasan untuk itu sebelum bantahan dilakukan. Di dalam kesimpulan itu boleh dimasukkan tangkisan tentang ketidakwenangan hakim, menyimpang dari apa yang ditentukan dalam pasal 114 dan bila ini tidak terjadi dianggap tidak diajukan, kecuali bila hakim tidak berwenang berdasarkan pokok perselisihan. Bila penggugat berpendapat ada alasan-alasan untuk memanggil seseorang untuk menanggungnya, maka ia harus mengajukan permohonan untuk itu dengan kesimpulan yang disertai alasan-alasan pada hari ia harus mengajukan jawaban balik (replik). Jika permohonan dikabulkan, maka hakim akan memberikan waktu yang cukup berdasarkan jarak ke tempat tinggal si penanggung dan menentuka hari untuk memeriksa perkara pokoknya maupun perkara penanggung. (rv. 99.) Putusan yang mengabulkan permohonan penanggung tidak perlu diberitahukan kepada penanggung. Hal itu dimasukkan dalam gugatan dan diserahkan tindakan-tindakannya yang harus disampaikan kepada penggugat dan penanggung. Bila permohonan ditolak, pada putusan ituhakim menentukan hari pada waktu mana diadakan panggilan setelah perkara itu dimasukkan kembali dalam daftar giliran siding”. Secara sederhana ada pihak ketiga yang ditarik untuk bertanggung jawab, biasanya oleh tergugat agar terlepas dari tuntutan pihak penggugat.