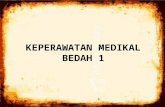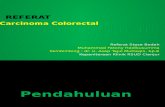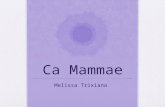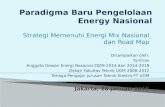BAB II ca nsfrg
-
Upload
fahlevie-epin -
Category
Documents
-
view
13 -
download
5
description
Transcript of BAB II ca nsfrg
BAB IITINJAUAN PUSTAKA2.1 Anatomi dan FisiologiNasofaring merupakan lubang sempit yang terdapat pada belakang rongga hidung. Bagian atap dan dinding belakang dibentuk oleh basis sphenoid, basis occiput dan ruas pertama tulang belakang. Nasofaring terletak dibelakang rongga hidung, di atas soft palatum. Bagian atap dan dinding belakang dibentuk oleh korpus ossis sphenoidalis, basis occiput dan ruas pertama tulang belakang. Kumpulan jaringan limfoid yang disebut tonsila faringeal terdapat di dalam submukosa daerah ini. Dasar dibentuk oleh permukaan atas soft palatum. Dinding anterior dibentuk oleh aperture nasalis posterior, dipisahkan oleh pinggir posterior septum nasi. Bagian depan berhubungan dengan rongga hidung melalui koana. Orificium dari tuba eustachii berada pada dinding samping dan pada bagian depan dan belakang terdapat ruangan berbentuk koma yang disebut dengan torus tubarius. Bagian atas dan samping dari torus tubarius merupakan reses dari nasofaring yang disebut dengan fossa rosenmuller. Nasofaring berhubungan dengan orofaring pada bagian soft palatum11.
Bangunan-bangunan penting yang terdapat di nasofaring adalah: 21. Ostium tuba eustachii pars pharyngealTuba eustachii merupakan kanal yang menghubungkan kavum nasi dan nasopharyng dengan rongga telinga tengah. Mukosa ostium tuba tidak datar tetapi menonjol seperti menara, disebut torus tubarius.2. Adenoid atau Tonsila LushkaBangunan ini hanya terdapat pada anak-anak usia kurang dari 13 tahun. Pada orang dewasa struktur ini telah mengalami regresi.3. Fosa Nasofaring atau Forniks NasofaringStruktur ini berupa lekukan kecil yang merupakan tempat predileksi fibroma nasofaring atau angiofibroma nasofaring.4. Fosa RosenmulleriFossa Rosenmulleri adalah lekukan kecil dibelakang torus tubarius. Daerah ini merupakan tempat predileksi karsinoma nasofaring. Lekuk kecil ini diteruskan ke bawah belakang sebagai alur kecil yang disebut sulkus salfingo-faring. Fossa Rosenmulleri merupakan tempat perubahan atau pergantian epitel dari epitel kolumnar/kuboid menjadi epitel pipih. Mukosa atau selaput lendir nasofaring terdiri dari epitel yang bermacam-macam, yaitu epitel kolumnar simpleks bersilia, epitel kolumnar berlapis, epitel kolumnar berlapis bersilia, dan epitel kolumnar berlapis semu bersilia. Ackerman dan Del Regato (1954) berpendapat bahwa epitel semu berlapis pada nasofaring ke arah mulut akan berubah mejadi epitel pipih berlapis. Demikian juga epitel yang ke arah palatum molle, batasnya akan tajam dan jelas sekali. Pendapat yang paling umum adalah asal tumor ganas nasofaring itu adalah tempat-tempat peralihan atau celah-celah epitel yang masuk ke jaringan limfe di bawahnya.2Walaupun fosa Rosenmulleri atau dinding lateral nasofaring merupakan lokasi keganasan tersering, tapi keganasan dapat juga terjadi di tempat-tempat lain di nasofaring.2 Keganasan nasofaring dapat juga terjadi pada:1. Dinding atas nasofaring atau basis kranii dan tempat di mana terdapat adenoid. 2. Di bagian depan nasofaring yaitu terdapat di pinggir atau di luar koana. 3. Dinding lateral nasofaring mulai dari fosa Rosenmulleri sampai dinding faring dan palatum molle.
2.2 DefinisiKarsinoma nasofaring adalah karsinoma yang terjadi pada lapisan epitel di nasofaring. Tumor ini menunjukkan derajat diferensiasi yang bervariasi dan sering tampak pada fossa Rosenmuller dan dapat menyebar kedalam atau keluar nasofaring menuju dinding lateral, posterosuperior, dasar tengkorak, palatum, kavum nasi, dan orofaring serta metastasis ke kelenjar limfe leher11.
2.3 EpidemiologiRas Mongoloid merupakan faktor dominan timbulnya karsinoma nasofaring, sehingga sering terjadi pada penduduk Cina bagian selatan, Hongkong, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Daerah Cina bagian selatan masih menduduki tempat tertinggi, yaitu mencapi 2500 kasus baru per tahun atau prevalensi 39,84 per 100.000 penduduk untuk Propinsi Guangdong 7,11. Penyakit ini juga ditemukan pada orang-orang yang hidup di daerah iklim dingin, hal ini diduga karena penggunaan pengawet nitrosamine pada makanan-makanan yang mereka simpan 1, 7, 11.Karsinoma nasofaring merupakan tumor ganas daerah kepala dan leher yang terbanyak ditemukan di Indonesia, jumlahnya mencapai 60% dari jumlah keseluruhan tumor ganas daerah kepala dan leher. Di semua pusat pendidikan dokter di Indonesia dari tahun ke tahun, karsinoma nasofaring selalu menempati urutan pertama di bidang THT. Frekuensinya hampir merata di setiap daerah. Catatan dari berbagai rumah sakit menunjukkan bahwa karsinoma nasofaring menduduki urutan ke empat setelah kanker leher rahim, kanker payudara dan kanker kulit.112.4 Etiologi dan Faktor Resiko Beberapa literatur menyebutkan bahwa penyebab karsinoma nasofaring adalah Virus Epstein-Barr (EB), karena pada hampir semua pasien dengan karsinoma nasofaring didapatkan titer anti-virus EB yang cukup tinggi, sedangkan pada penderita karsinoma lain di saluran pernapasan bagian atas tidak ditemukan titer antibodi terhadap kapsid virus EB ini. Kaitan antara virus Epstein-Barr dan konsumsi ikan asin yang diawetkan dengan nitrosamin dikatakan sebagai penyebab utama timbulnya penyakit ini. Kebiasaan untuk mengkonsumsi ikan asin dengan nitrosamine secara terus menerus mulai dari masa kanak-kanak, merupakan mediator utama yang dapat mengaktifkan virus ini sehingga menimbulkan karsinoma nasofaring. Banyak penelitian mengenai perilaku virus ini dikemukakan, tetapi virus ini bukan merupakan satu-satunya faktor, karena banyak faktor lain yang sangat mempengaruhi munculnya tumor ganas ini seperti letak geografis, ras, jenis kelamin, genetik, pekerjaan, lingkungan, kebiasaan hidup, kebudayaan, sosial ekonomi, infeksi bakteri atau parasit. 1,2,11Tumor ganas ini sering ditemukan pada laki-laki dengan perbandingan 4:1 dan sebabnya belum dapat diungkapkan dengan pasti apakah terdapat hubungan dengan faktor genetik, hormonal, kebiasaan hidup, pekerjaan dan lain-lain. Pada penelitian yang dilakukan di Medan (2008), ditemukan perbandingan penderita laki-laki dan perempuan 3 : 2. Hormon testosteron yang dominan pada laki-laki dicurigai mengakibatkan penurunan respon imun dan surviellance tumor sehingga laki-laki lebih rentan terhadap infeksi VEB dan kanker.1,7,11Faktor lingkungan yang berpengaruh adalah iritasi kronik oleh bahan kimia, asap sejenis kayu tertentu, kebiasaan memasak dengan bahan atau bumbu masak tertentu dan kebiasan makan makanan yang terlalu panas. Karsinoma nasofaring tidak termasuk tumor genetik, tetapi kerentanan terhadap karsinoma nasofaring pada kelompok masyarakat tertentu relatif lebih menonjol dan memiliki agregasi familial. Analisis korelasi menunjukkan gen HLA (human leukocyte antigen) dan gen pengkode enzim sitokrom p4502E (CYP2E1) kemungkinan adalah gen kerentanan terhadap karsinoma nasofaring, mereka berkaitan dengan sebagian besar karsinoma nasofaring. Sebagian besar pasien adalah golongan sosial ekonomi rendah dan hal ini menyangkut pula dengan keadaan lingkungan dan kebiasaan hidup. 2,112.5 PatofisiologiKeganasan pada umumnya dapat terjadi melalui dua mekanisme yaitu, pertama pemendekan waktu siklus sel sehingga akan menghasilkan lebih banyak sel yang diproduksi dalam satuan waktu. Kedua, penurunan jumlah kematian sel akibat gangguan pada proses apoptosis. Gangguan pada berbagai protoonkogen dan gen penekan tumor (TSGs) yang menghambat penghentian proses siklus sel. 9,11Pada keadaan fisiologis proses pertumbuhan, pembelahan, dan diferensiasi sel diatur oleh gen yang disebut protoonkogen yang dapat berubah menjadi onkogen bila mengalami mutasi. Onkogen dapat menyebabkan kanker karena memicu pertumbuhan dan pembelahan sel secara patologis.9,11
Gambar 2.3 Skema Patofisiologi Terjadinya Keganasan 9
Virus Epstein-Barr (EBV) bereplikasi dalam sel-sel epitel dan menjadi laten dalam limfosit B. Infeksi EBV terjadi pada dua tempat utama yaitu sel epitel kelenjar saliva dan sel limfosit. EBV memulai infeksi pada limfosit B dengan cara berikatan dengan reseptor virus, yaitu komponen komplemen C3d (CD21 atau CR2). Glikoprotein (gp350/220) pada kapsul EBV berikatan dengan protein CD21 dipermukaan limfosit B3. Aktivitas ini merupakan rangkaian yang berantai dimulai dari masuknya EBV ke dalam DNA limfosit B dan selanjutnya menyebabkan limfosit B menjadi immortal. Sementara itu, sampai saat ini mekanisme masuknya EBV ke dalam sel epitel nasofaring belum dapat dijelaskan dengan pasti. Namun demikian, ada dua reseptor yang diduga berperan dalam masuknya EBV ke dalam sel epitel nasofaring yaitu CR2 dan PIGR (Polimeric Immunogloblin Receptor). Sel yang terinfeksi oleh EBV dapat menimbulkan beberapa kemungkinan yaitu : sel menjadi mati bila terinfeksi dengan EBV dan virus mengadakan replikasi, atau EBV yang menginfeksi sel dapat mengakibatkan kematian virus sehingga sel kembali menjadi normal atau dapat terjadi transformasi sel yaitu interaksi antara sel dan virus sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan sifat sel sehingga terjadi transformasi sel menjadi ganas sehingga terbentuk sel kanker.2,11Tumor ganas mempunyai kemampuan menginvasi dan merusak sistem barier yang ada. Tumor yang tumbuh di garis tengah nasofaring dapat menyebar ke salah satu sisi atau sering bilateral. Jalan yang paling sering dilalui oleh penyebaran tumor yaitu3:a. Lumen/ Ruang Nasofaring Jalan ini sering terjadi pada tumor yang sangat besar dan akan masuk dalam orofaring atau kavum nasi. Kadang-kadang dapat masuk ke sinus maksila atau orbita, tetapi sangat jarang masuk ke tuba Eustachius. b. Ruang Retrofaring Walaupun sering melalui jalan anatomis (retroparotidian), kadang-kadang tumor dapat langsung masuk ke ruang retrofaring dengan mengadakan kompresi atau infiltrasi ke ruang retrostiloid atau merusak bagian lateral vertebra servikais pertama (vertebra atlas). c. Ruang Parafaring 1. Ruang kecil prestiloid, tumor yang tumbuh di dinding lateral atau di daerah fossa Rosenmuller dapat menjalar ke ruang kecil ini yang terletak di atasnya dan akan mengenai serabut motorik dan sensorik saraf trigeminus (V). Tumor dapat menginvasi otot pterigoid dan menyebabkan trismus atau menginfiltrasi otot levator sehingga menyebabkan asimetri palatum mole. Tumor juga dapat mengenai palatum durum, kelenjar parotis fisura pterigomaksila dan ke fossa infratemporal. Pada tumor yang sangat besar dapat menginvasi sinus maksila dan frontalis. 2. Ruang kecil retrostiloid, ruang kecil ini berisi selubung karotis dan isinya, kelenjar limfe servikal dalam atas, saraf-saraf kranial terakhir (saraf IX,X,XI,XII) dan cabang saraf simpatis servikalis. Ruang ini disebut juga ruang retroparotidian yang selain dapat terinvasi melalui jalan anatomis (melalui aliran limfe/ retroparotidian) dapat juga akibat lanjutan invasi langsung yang lebih dalam ruang parafaring. Dari ruang ini pula tumor dapat menyebabkan erosi dasar tengkorak. d. Intrakranial Perluasan tumor ke intrakranial biasanya melalui foramen laserum dan ovale atau melalui sinus kavernosus dan ganglion gaseri dan mengenai saraf kranial otot bola mata, yaitu saraf III,IV,VI (penyebarab secara petrosfenoid) tetapi dapat juga melalui erosi dasar kanalis karotis dan melalui arteri karotis interna masuk ke dalam sinus kavernosus, juga dapat akibat tumor mendestruksi sinus sfenoid.e.Tumor menyebar langsungke sinus etmoid, selanjutnya mengenai sinus frontalis, maksila, dan rongga orbita. f. Metastasis jauh Metastasis jauh dapat melalui aliran darah atau sistem limfatik dan mengenai hati, tulang, dan paru.
2.6 Manifestasi KlinisKeluhan penderita KNF berhubungan dengan lokasi tumor primer, derajat, dan arah penyebarannya12:1. Gejala Dini Menegakkan diagnosis KNF secara dini merupakan hal yang paling penting dalam menurunkan angka kematian akibat penyakit ini. Gejala dini berupa: Gejala Telingaa. Oklusi tuba Eustachius/ kataralis Pada umumnya tumor bermula di fosa Rosenmuller dan pertumbuhannya dapat menyebabkan penyumbatan muara tuba eustakhius. Pasien mengeluh rasa penuh ditelinga, rasa berdengung kadang-kadang disertai dengan gangguan pendengaran yang biasanya tuli konduktif dan bersifat unilateral. Gejala ini merupakan gejala yang sangat dini dari karsinoma nasofaring. Perlu diperhatikan jika gejala ini menetap atau sering timbul tanpa penyebab yang jelas.b. Gangguan pendengaran Sering bersifat tuli konduktif dan unilateral. Gejala ini disebabkan karena otitis media serosa akibat gangguan fungsi tuba. Tuli saraf mungkin terjadi pada penderita KNF sebagai efek radioterapi dan jarang akibat penyebaran langsung tumor ke saraf VIII. c. Otitis media serosa sampai perforasi membran timpani Penyebabnya adalah sumbatan muara tuba Eustachius oleh massa tumord. Tinnitus Sering dijumpai pada penderita KNF, dapat mengganggu dan sulit diobati. Gejala ini juga disebabkan gangguan fungsi tuba. e. Otalgia Gejala ini jarang ditemukan dan bila ada menunjukkan bahwa tumor telah menginfiltrasi daerah parafaring dan mengerosi dasar tengkorak.
Gejala Hidung2,12Dinding tumor biasanya rapuh sehingga apabila terjadi iritasi ringan dapat terjadi epistaksis. Keluarnya darah ini biasanya berulang-ulang, biasanya jumlahnya sedikit bercampur dengan ingus, sehingga berwarna merah jambu. Sumbatan hidung yang menetap terjadi akibat pertumbuhan tumor kedalam rongga nasofaring dan menutupi koana. Gejala menyerupai pilek kronis, kadang-kadang disertai dengan gangguan penciuman dan adanya ingus kental. Harus dicuriga iadanya karsinoma nasofaring, bila ada gejala-gejala: Bila penderita mengalami pilek lama, lebih dari 1 bulan, terutama penderita usia lebih dari 40 tahun, sedang pada pemeriksaan hidung terdapat kelainan. Bila penderita pilek dan keluar sekret yang kental, berbau busuk, lebih-lebih jika terdapat titik atau garis perdarahan tanpa kelainan di hidung atau sinus paranasal. Pada penderita yang berusia lebih dari 40 tahun, sering keluar darah dari hidung (epistaksis) sedangkan pemeriksaan tekanan darah normal dan pemeriksaan hidung tidak ada kelainan.2. Gejala lanjut12a. Limfadenopati servikal Melalui aliran pembuluh limfe, sel-sel kanker dapat sampai di kelenjar limfe leher dan tertahan di sana karena memang kelenjar ini merupakan pertahanan pertama agar sel-sel kanker tidak langsung mengalir ke bagian tubuh yang lebih jauh. Ditandai dengan pembesaran kelenjar limfe regional yang merupakan penyebaran terdekat secara limfogen dari KNF. Dapat terjadi unilateral atau bilateral. Kelenjar limfe retrofaringeal (Rouviere) merupakan tempat pertama penyebaran sel tumor ke kelenjar, tetapi pembesaran kelenjar limfe ini tidak teraba dari luar. Benjolan ini tidak dirasakan nyeri karenanya sering diabaikan oleh pasien. Ciri yang khas penyebaran KNF ke kelenjar limfe leher yaitu terletak di bawah prosesus mastoid (kelenjar limfe jugulodigastrik), dibawah angulus mandibula, di dalam otot sternocleidomastoid, konsistensi keras, tidak terasa sakit, tidak mudah digerakkan terutama bila sel tumor telah menembus kelenjar dan mengenai jaringan otot dibawahnya. Lebih dari 40% dari seluruh kasus KNF, keluhan adanya tumor di leher ini yang paling sering dijumpai dan merupakan gejala utama yang mendorong pasien datang ke dokterb. Gejala Neurologis Sindroma petrosfenoidal , akibat penjalaran tumor primer ke atas melalui foramen laserum dan ovale sepanjang fosa kranii media sehingga mengenai saraf kranial anterior berturut-turut yaitu saraf VI, saraf III, saraf IV, sedangkan saraf II paling akhir mengalami gangguan. Dapat pula menyebabkan parese saraf V. Parese saraf II menyebabkan gangguan visus, parese saraf III menyebabkan kelumpuhan otot levator palpebra dan otot tarsalis superior sehingga menimbulkan ptosis, dan parese saraf III, IV, dan IV menyebabkan keluhan diplopia karena saraf-saraf tersebut berperan dalam pergerakan bola mata, dan saraf V (trigeminus) dengan keluhan rasa kebas di pipi dan wajah yang biasanya unilateral. Proses karsinoma yang lanjut akan mengenai saraf otak ke IX, X,XI,XII jika penjalaran melalui foramen jugulare. Dapat pula terjadi sindrom retroparotidian,yaitu terjadi akibat kelumpuhan n.IX,X,XI, dan XII. Biasanya beberapa saraf otak terkena secara unilateral, tetapi pada beberapa kasus pernah ditemukan bilateral. Nervus VII dan VIII, karena letaknya agak tinggi serta terletak dalam kanalis tulang, sangat jarang terkena tumor.3. Gejala Metastase Jauh Metastase jauh dari KNF dapat secara limfogen atau hematogen, yang dapat mengenai spina vertebra torakolumbar, femur, hati, paru, ginjal, dan limfa. Metastase jauh dari KNF terutama ditemukan di tulang (48%), paru-paru (27%), hepar (11%) dan kelenjar getah bening supraklavikula (10%). Metastase sejauh ini menunjukkan prognosis yang sangat buruk, biasanya 90% meninggal dalam waktu 1 tahun setelah diagnosis ditegakkan.
Gambaran KlinikDiagnosis KNF harus dimulai dengan mengetahui riwayat penyakit secara lengkap. Perkembangan gejala dari permulaan sampai yang terakhir sedapat mungkin diketahui dengan jelas. Penting untuk mengetahui gejala dini KNF dimana tumor masih terbatas di rongga nasofaring terutama pada orang dengan resiko tinggi yakni laki-laki usia diatas 40 tahun3.Kriteria klinik untuk suatu dugaan karsinoma nasofaring berdasarkan Digby score adalah sebagai berikut5Nilai
Masa terlihat pada nasofaring25
Limfadenopati di leher25
Gangguan pada hidung yang khas15
Gangguan pada telinga yang khas5
Karakteristik terhadap gangguan satu atau lebih dari paralisa syaraf5
Sakit kepala unilateral/bilateral5
Eksoptalmus5
Jumlah keseluruhan akan dikurangi 10 jika usia penderita dibawah 15 tahun. Demikian juga jika usia penderita antara 15 tahun sampai 25 tahun dengan frog face jumlah keseluruhan akan dikurangi 10. Jika jumlah keseluruhan mencapai 50, maka diagnosa sementara karsinoma nasofaring dapat ditegakkan, sementara menunggu hasil pemeriksaan penunjang lainnya.
DAFTAR PUSTAKA
1. American Cancer Society. 2011. Nasopharyngeal Cancer. Available at : http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/003124-pdf.pdf. Diakses pada tanggal : 17 Februari 2014.2. Bambang S. 1992. Diagnostik dan Pengelolaan Kanker Telinga, Hidung, Tenggorok dan Kepala Leher. Semarang : Fakultas Kedokteran Universitas Diponogoro.3. Brennan, B., 2006. Nasopharyngeal Carcinoma. BioMed Central Ltd. USA. Available at: http://www.malattiemetaboliche.it/articoli/articoli/nasopharyngeal_carcinoma.pdf. (di akses pada tanggal 21 Maret 2014).4. Desen, W., 2008. Buku ajar onkologi klinis edisi kedua. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jakarta. 263-278.5. Digby. H. K. 1951. Nasopharyngeal Carcinoma. Available at : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2238562/pdf/annrcse00052-0047.pdf. Diakses pada tanggal : 22 Maret 2014.6. Fibrian. C.K. 2010. Review Article: Association Between Histopatological Classification With Response to Chemoradiation Theraphy Based on CT Scan Imaging of Carcinoma Nasopharynx Patients. Available at : http://eprints.undip.ac.id/23402/1/Kartika.pdf. Di akses tanggal : 17 Februari 2014.7. Jeyakumar, anita et al. 2006. Review of Nasopharyngeal Carcinoma ENT-Ear, Nose & Throat Journal.8. Laksmi. I. L. 2009. Tampilan Immunositokimia HE R2/NEU Pada Biopsi Aspirasi Metastasis Karsinoma Nasofaring Kelenjar Limfe. Tesis. Medan : FK USU.9. Maitra, Anirban dan Kumar, Vinay. 2007. Paru dan Saluran Napas Atas. Disunting oleh Vinay Kumar Ramzi S Cotran, dan Stanley L. Robbins. Buku Ajar Patologi Robbins, Ed. 7, Vol.2. Jakarta : EGC.10. NCCN Clinical Practice Guideline in Oncology. 2011. Head and Neck Cancer. Available at: http://oralcancerfoundation.org/treatment/pdf/head-and-neck.pdf. Diakses pada tanggal 22 Februari 2014.11. Roezin, A., dan Marlinda A. 2010. Karsinoma Nasofaring. dalam: Soepardi, Efianty A., Nurbaiti I., Jenny B., dkk. 2010. Buku Ajar Ilmu Kesehatan Telinga-Hidung-Tenggorok Kepala Leher edisi keenam. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jakarta. 182-190.12. Soetjipto, D., 1989. Karsinoma Nasofaring. Dalam: Iskandar, N., Masrin M., Dan Damayanti S. Tumor-hidung-tenggorok diagnose & penatalaksanaan. Fakultas kedokteran universitas Indonesia. 71-83.