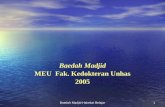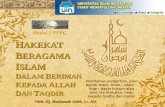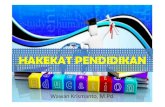BAB I HAKEKAT GEOGRAFI A. Pengertian Geografi · HAKEKAT GEOGRAFI A. Pengertian Geografi Istilah...
Transcript of BAB I HAKEKAT GEOGRAFI A. Pengertian Geografi · HAKEKAT GEOGRAFI A. Pengertian Geografi Istilah...

1
BAB I HAKEKAT GEOGRAFI
A. Pengertian Geografi
Istilah Geografi berasal dari bahasa Yunani Geo yang artinya bumi dan
Graphien yang artinya pencitraan. Geografi adalah ilmu pengetahuan yang
menggambarkan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Beberapa definisi
Geografi yang dikemukakan para ahli geografi, antara lain sebagai berikut.
Menurut Prof. Bintarto dalam papernya berjudul Suatu Tinjauan Filsafat
Geografi mengemukakan definisi Geografi sebagai berikut: Geografi mempelajari
hubungan kausal gejala-gejala di muka bumi dan peristiwa-peristiwa yang
terjadi di muka bumi baik yang fisikal maupun yang menyangkut mahkluk hidup
beserta permasalahannya, melalui pendekatan keruangan, ekologikal dan
regional untuk kepentingan program, proses dan keberhasilan pembangunan
(Bintarto, 2000).
Menurut Vernor E. Finch dan Glen Trewartha (1980) Geografi adalah
deskripsi dan penjelasan yang menganalisis permukaan bumi dan
pandangannya tentang hal yang selalu berubah dan dinamis, tidak statis dan
tetap. Dari pengertian di atas Vernor & Glen menitikberatkan pada aspek fisik
yang ada di bumi yang selalu berubah dari masa ke masa. Contoh: perubahan
cuaca maupun iklim pada suatu tempat atau wilayah dan perubahan kesuburan
tanah akibat dari proses erosi dan pelapukan yang sangat tinggi.
Kajian ilmu geografi yang paling utama adalah menelaah bumi dalam
konteks hubungannya dengan
B. Ruang Lingkup Ilmu Geografi
Ruang lingkup ilmu geografi secara umum adalah sama luasnya dengan
objek studi yang menjadi kajian dari ilmu geografi, yaitu meliputi semua gejala

2
geosfer, baik gejala alam maupun gejala sosial, serta interaksi antara manusia
dengan lingkungannya. Ruang lingkup studi ilmu geografi yaitu:
1. Kajian terhadap wilayah (region);
2. Interaksi antara manusia dengan lingkungan fisik yang merupakan salah
satu bagian dari keanekaragaman wilayah;
3. Persebaran dan kaitan antara penduduk (manusia) dengan aspek-aspek
keruangan dan usaha manusia untuk memanfaatkannya.
Kenyataan yang ada sekarang ini, ketiga ruang lingkup ilmu geografi
tersebut telah terintegrasi pada suatu analisis wilayah (region). Hal ini
disebabkan karena analisis suatu wilayah pada hakikatnya adalah kajian yang
komprehensif dan terpadu antara unsur-unsur yang ada di wilayah tersebut,
seperti unsur lokasi, fisik, sosial juga interaksi dan interrelasi antar unsur.

3
C. Objek Studi Geografi
Objek studi geografi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu objek
material dan objek formal.
1. Objek Material
Objek material geografi adalah sasaran atau isi kajian geografi. Objek
material yang umum dan luas adalah geosfer (lapisan bumi), yang meliputi:
a. Litosfer (lapisan keras), merupakan lapisan luar dari bumi kita. Lapisan ini
disebut kerak bumi dalam ilmu geologi.
b. Atmosfer (lapisan udara), terutama adalah lapisan atmosfer bawah yang
dikenal sebagai troposfer.
c. Hidrosfer (lapisan air), baik yang berupa lautan, danau, sungai dan air
tanah.
d. Biosfer (lapisan tempat hidup), yang terdiri atas hewan, tumbuhan, dan
manusia sebagai suatu komunitas bukan sebagai individu.
e. Pedosfer (lapisan tanah), merupakan lapisan batuan yang telah mengalami
pelapukan, baik pelapukan fisik, organik, maupun kimia.
Jadi secara nyata objek material geografi meliputi gejala-gejala yang
terdapat dan terjadi di muka bumi, seperti aspek batuan, tanah, gempa bumi,
cuaca, iklim, gunung api, udara, air serta flora dan fauna yang terkait dengan
kehidupan manusia.
2. Objek Formal
Objek formal adalah sudut pandang dan cara berpikir terhadap suatu
gejala di muka bumi, baik yang sifatnya fisik maupun sosial yang dilihat dari
sudut pandang keruangan (spasial). Dalam geografi selalu ditanyakan mengenai
di mana gejala itu terjadi, dan mengapa gejala itu terjadi di tempat tersebut. Di
sini ilmu geografi diharapkan mampu menjawab berbagai pertanyaan sebagai
berikut.

4
a. Apa (what), berkaitan dengan struktur, pola, fungsi dan proses gejala
atau kejadian di permukaan bumi.
b. Di mana (where), berkaitan dengan tempat atau letak suatu objek
geografi di permukaan bumi.
c. Berapa (how much/many), berkaitan dengan hal-hal yang menyatakan
ukuran (jarak, luas, isi, dan waktu) suatu objek geografi dalam bentuk
angka-angka.
d. Mengapa (why), berkaitan dengan rangkaian waktu dan tempat, latar
belakang, atau interaksi dan interdependensi suatu gejala, peristiwa, dan
motivasi manusia.
e. Bagaimana (how), berkaitan dengan penjabaran suatu pola, fungsi, dan
proses gejala dan peristiwa.
f. Kapan (when), berkaitan dengan waktu kejadian yang berlangsung, baik
waktu yang lampau, sekarang, maupun yang akan datang.
g. Siapa (who), berkaitan dengan subjek atau pelaku dari suatu kejadian
atau peristiwa.
D. Aspek-Aspek Geografi dan Gejala-Gejalanya Dalam Kehidupan
1. Aspek Geografi
Secara garis besar, dalam menelaah dan mengkaji geografi dapat
diklasifikasikan menjadi geografi fisik, geografi manusia, dan geografi regional.
a. Geografi Fisik
Geografi fisik adalah cabang dari ilmu geografi yang mempelajari
gejala fisik dari permukaan bumi yang meliputi tanah, air, dan udara
dengan segala prosesnya. Selain itu, geografi fisik juga mengkaji gejala-
gejala alamiah permukaan bumi yang menjadi lingkungan hidup manusia.
Geografi fisik dapat dijadikan pelengkap dalam mempelajari geografi
manusia, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan.

5
Sesuai dengan pembagian geografi ortodok, geografi fisik terdiri
atas geomorfologi, hidrologi, klimatologi, pedologi, dan lain-lain.
b. Geografi manusia
Geografi manusia adalah cabang dari ilmu geografi yang
mempelajari semua aspek gejala di permukaan bumi yang mengambil
manusia sebagai objek utamanya. Sesuai dengan pembagian geografi
ortodok, geografi manusia dapat dibagi menjadi geografi ekonomi,
geografi penduduk, geografi perkotaan, dan geografi pedesaan.
c. Geografi regional
Geografi regional merupakan perpaduan dari geografi fisik dan
geografi manusia. Geografi regional merupakan studi tentang variasi
persebaran gejala dalam ruang pada waktu tertentu baik lokal, nasional,
maupun kontinental. Melalui analisis geografi regional, karakteristik yang
khas dari suatu wilayah dapat ditonjolkan, sehingga perbedaan wilayah
dapat terlihat jelas. Dalam studi geografi regional, semua gejala geografi
ditinjau dan dideskripsikan secara berkaitan dalam hubungan integrasi
dan interrelasi keruangan.

6
2. Gejala Geografi Dalam Kehidupan Sehari-Hari
Beberapa gejala geografi yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari
antara lain cuaca, iklim, gempa bumi, vulkanisme, angin, dan lain-lain.
a. Cuaca
Cuaca adalah keadaan rata-rata pada suatu tempat, meliputi
daerah yang sempit, dan waktunya relatif singkat. Cuaca sangat
mempengaruhi kehidupan manusia di muka bumi. Keadaan cuaca dapat
diperkirakan dengan cara pengamatan. Pengamatan dilakukan terhadap
unsur-unsur cuaca misalnya suhu udara, tekanan udara, kelembapan,
angin, keadaan awan, dan curah hujan.
b. Iklim
Iklim merupakan rata-rata keadaan cuaca pada suatu wilayah
yang luas dan dalam waktu yang lebih lama. Iklim sangat berpengaruh
pada pergantian musim yang ada di Indonesia. Keberadaan musim
penghujan dan musim kemarau di Indonesia sangat berpengaruh pada
kehidupan petani khususnya untuk kelangsungan hidup tanaman-
tanaman semusim, di mana pada musim kemarau petani akan menanam
palawija dan pada musim penghujan petani akan menanam padi.
Keadaan iklim dipermukaan bumi sangat bervariasi tergantung pada
letak lintang dan bentuk daerah. Unsur-unsur iklim antara lain, pola suhu
atau temperatur udara, pola tekanan udara, dan pola kelembapan udara.
c. Gempa Bumi
Gempa bumi adalah gejala alam yang mempengaruhi kehidupan
manusia. Gempa bumi dapat dibedakan menjadi tiga yaitu gempa bumi
runtuhan (terban), gempa bumi tektonik, dan gempa bumi vulkanik.
Contoh, gempa bumi tektonik adalah gempa yang terjadi di Yogyakarta
dan sebagian Jawa Tengah yang banyak menimbulkan korban jiwa dan
rusaknya bangunan yang ada di wilayah tersebut. Manusia sampai saat

7
ini hanya bisa meramalkan akan adanya gempa bumi, tetapi belum bisa
memastikan kapan terjadinya gempa bumi, sehingga hal yang terpenting
adalah kewaspadaan penyelamatan diri ketika terjadi bencana tersebut.
d. Vulkanisme
Vulkanisme adalah peristiwa naiknya magma dari dalam perut
bumi menuju permukaan bumi. Magma merupakan campuran batu-
batuan dalam keadaan cair, liat, dan sangat panas. Aktivitas magma
sangat dipengaruhi oleh tingginya suhu magma dan banyaknya gas yang
terkandung di dalamnya. Magma dapat berbentuk gas, padat, dan cair.
Aktivitas gunung api tidak hanya menimbulkan kerugian tetapi juga
dapat memberikan keuntungan di antaranya daerah di sekitar gunung api
sangat subur sehingga hasil pertaniannya sangat besar.
e. Angin
Perbedaan tekanan udara di beberapa tempat menimbulkan aliran
udara dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat bertekanan rendah
yang disebut dengan angin. Untuk mengetahui arah angin dapat
digunakan bendera angin dan untuk mengetahui kecepatan angin di
gunakan alat yang di sebut dengan anemometer. Angin terjadi sepanjang
tahun atau setiap musim dengan intensitas yang berbeda-beda. Angin
sangat diperlukan manusia, khususnya bagi para nelayan yang
menggantungkan pada arah dan kecepatan angin dalam aktivitasnya
mencari ikan di laut.

8
BAB II DINAMIKA KEPENDUDUKAN
A. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Dinamika Penduduk
Jumlah penduduk dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu yaitu
bertambah atau berkurang. Dinamika penduduk atau perubahan jumlah
penduduk dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor yaitu: Kelahiran (natalitas); Kematian
(mortalitas); dan Migrasi (perpindahan).
Jumlah kelahiran dan kematian sangat menentukan dalam pertumbuhan
penduduk Indonesia, oleh karena itu kita perlu mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi kelahiran dan kematian.
1. Faktor yang menunjang dan menghambat kelahiran (natalitas) di Indonesia
adalah sebagai berikut:
a. Penunjang Kelahiran (Pro Natalitas) antara lain :
1) Kawin usia muda
2) Pandangan “banyak anak banyak rezeki”
3) Anak menjadi harapan bagi orang tua sebagai pencari nafkah
4) Anak merupakan penentu status social
5) Anak merupakan penerus keturunan terutama anak laki-laki.
b. Penghambat Kelahiran (Anti Natalitas) antara lain :
1) Pelaksanan Program Keluarga Berencana (KB)
2) Penundaan usia perkawinan dengan alasan menyelesaikan pendidikan
3) Semakin banyak wanita karir
c. Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate /CBR) adalah jumlah kelahiran hidup
dari tiap 1000 orang penduduk dalam waktu satu tahun. Rumusnya adalah :

9
Contoh : Jumlah penduduk suatu negara tahun 2000 adalah 25.000.000 jiwa.
Jumlah kelahiran dalam setahun sebanyak 800.000 jiwa. Hitunglah angka
kelahiran negara tersebut ?
Hal ini berarti setiap 1000 orang penduduk, rata-rata kelahirannya 32 orang
bayi dalam setahun.
Penggolongan angka kelahiran kasar (CBR):
a. Angka kelahiran rendah apabila kurang dari 30 per 1000 penduduk
b. Angka kelahiran sedang, apabila antara 30 – 40 per 1000 penduduk
c. Angka kelahiran tinggi, apabila lebih dari 40 per 1000 penduduk
2. Faktor yang menunjang dan menghambat kematian (mortalitas) di Indonesia,
adalah sebagai berikut :
a. Penunjang Kematian (Pro Mortalitas) antara lain :
1) Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan
2) Fasilitas kesehatan yang belum memadai
3) Keadaan gizi penduduk yang rendah
4) Terjadinya bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir
5) Peparangan, wabah penyakit, pembunuhan
b. Penghambat Kematian (Anti Mortalitas) antara lain :
1) Meningkatnya kesadaran penduduk akan pentingnya kesehatan
2) Fasilitas kesehatan yang memadai
3) Meningkatnya keadaan gizi penduduk
4) Memperbanyak tenaga medis seperti dokter, dan bidan
5) Kemajuan di bidang kedokteran.

10
c. Angka Kematian Kasar (Crude Death Rate) adalah jumlah kematian setiap
1000 penduduk dalam waktu satu tahun. Rumusnya adalah :
Contoh : Jumlah penduduk suatu negara tahun 2000 adalah 21.000.000 jiwa.
Jumlah kelahiran dalam setahun sebanyak 315.000 jiwa. Hitunglah angka
kelahiran kasar negara tersebut ?
Hal ini berarti setiap 1000 orang, penduduk yang meninggal rata-rata 15
orang dalam setahun.
Penggolongan angka kelahiran kasar :
a. Angka kematian rendah apabila kurang dari 10 per 1000 penduduk
b. Angka kematian sedang, apabila antara 10 – 20 per 1000 penduduk
c. Angka kematian tinggi, apabila lebih dari 20 per 1000 penduduk

11
BAB III POLA PEMUKIMAN PENDUDUK
A. Pendahuluan
Gambar 3.1 Pola Pemukiman
Pola Pemukiman Terpusat
Pola Pemukiman Linier
Pola pemukiman berdasarkan kultur penduduk
Adanya pemukiman penduduk di dataran rendah dan dataran tinggi
sangat berkaitan dengan perbedaan potensi fisik dan non fisik suatu wilayah.
Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam pola pemukiman
penduduk di suatu wilayah.

12
B. Definisi Pola Pemukiman Penduduk
Pola pemukiman menunjukkan tempat bermukim manusia dan
bertempat tinggal menetap dan melakukan kegiatan/aktivitas sehari-harinya.
Permukiman dapat diartikan sebagai suatu tempat (ruang) atau suatu daerah
dimana penduduk terkonsentrasi dan hidup bersama menggunakan lingkungan
setempat, untuk mempertahankan, melangsungkan, dan mengembangkan
hidupnya. Pengertian pola dan sebaran pemukiman memiliki hubungan yang
sangat erat. Sebaran permukiman membincangkan hal dimana terdapat
permukiman dan atau tidak terdapat permukiman dalam suatu wilayah,
sedangkan pola pemukiman merupakan sifat sebaran, lebih banyak berkaitan
dengan akibat faktor-faktor ekonomi, sejarah dan faktor budaya.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pola pemukiman
penduduk adalah bentuk persebaran tempat tinggal penduduk berdasarkan
kondisi alam dan aktivitas penduduknya.
Gambar 3.2. Pola pemukiman penduduk mengikuti jalan raya
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pola Pemukiman Penduduk
Kalau diperhatikan, ternyata bentuk atau pola pemukiman antara daerah
satu dengan daerah lain mempunyai perbedaan. Perbedaan tersebut terjadi,
karena faktor geografi yang berbeda. Secara umum adanya perbedaan pola
pemukiman penduduk dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

13
1. Relief (Perbedaan Tinggi Rendhnya Permukaan Bumi)
Permukaan muka Bumi terdiri
dari berbagai relief seperti
pegunungan, dataran rendah,
perbukitan dan daerah pantai.
Kondisi ini menyebabkan
penduduk membuat pemukiman
yang sesuai dengan lingkungan
tempat ia berada.
2. Kesuburan Tanah
Tingkat kesuburan tanah di setiap
tempat berbeda-beda. Di daerah
pedesaan, lahan yang subur
merupakan sumber penghidupan
bagi penduduk. Oleh karena itu
mereka mendirikan tempat tinggal
berkumpul dan memusat dekat
dengan sumber penghidupannya.
Gambar 3.3. Rumah dekat dengan persawahan
Gambar 3.2. Relief suatu tempat
mempengaruhi keinginan penduduk
untuk bermukim

14
3. Keadaan Iklim
Faktor-faktor iklim seperti curah
hujan, intensitas radiasi Matahari
dan suhu di setiap tempat
berbeda-beda. Kondisi ini
akan berpengaruh terhadap
tingkat kesuburan tanah
dan kondisi alam daerah tersebut.
Kondisi ini akan berpengaruh
pada pola pemukiman penduduk
di daerah itu. Pada daerah dingin seperti pegunungan, dataran tinggi serta di
Kutub utara orang akan cenderung mendirikan tempat tinggal saling berdekatan
dan mengelompok. Sedangkan di daerah panas pemukiman penduduk
cenderung lebih terbuka dan agak terpencar.
4. Keadaan Ekonomi
Kegiatan ekonomi seperti
pusat-pusat perbelanjaan,
perindustrian, pertambangan,
pertanian, perkebunan dan
perikanan akan berpengaruh
pada pola pemukiman
yang mereka pilih, terutama
tempat tinggal yang dekat
dengan berbagai fasilitas yang
menunjang kehidupannya, karena hal itu akan memudahkan mereka dalam
memenuhi kebutuhan hidupnya.
Gambar 3.5. Pemukiman penduduk di daerah perkotaan
Gambar 3.4. Rumah dekat gunung

15
5. Kultur Penduduk
Budaya penduduk yang
dipegang teguh oleh suatu
kelompok masyarakat akan
berpengaruh pada pola
pemukiman kelompok
tersebut. Di beberapa daerah
tertentu seperti suku badui
di Banten, Suku Toraja
di Sulawesi Selatan, Suku Dayak di Kalimantan, cenderung memiliki pola
pemukiman mengelompok dan terisolir dari pemukiman lain.
a. Suku Toraja
Suku Toraja adalah suku yang
menetap di pegunungan bagian
utara Sulawesi Selatan.
Populasinya diperkirakan sekitar
600.000 jiwa. Mereka juga
menetap di sebagian dataran
Luwu dan Sulawesi Barat.
Tempat pemukiman suku Toraja
dikenal dengan Tana Toraja.
Rumah tradisional Toraja
disebut tongkonan.
Gambar 3.6. Pemukiman penduduk suku Toraja
Gambar 3.7. Pemukiman penduduk suku Toraja

16
b. Suku Baduy
Suku Baduy tinggal di pedalaman
Jawa Barat. Wilayah Baduy
meliputi Cikeusik, Cibeo, dan
Cikartawarna. Nama Baduy
sendiri diambil dari nama sungai
yang melewati wilayah itu sungai
Cibaduy. Di desa ini tinggal suku
Baduy Luar yang sudah banyak
berbaur dengan masyarakat
Sunda lainnya. Sedangkan suku
Baduy Dalam tinggal di pedalaman hutan dan masih terisolir dan belum masuk
kebudayaan luar. Orang Baduy dalam terkenal teguh dalam tradisinya.
c. Suku Kubu
Suku Kubu atau juga dikenal
dengan Suku Anak Dalam atau
Orang Rimba adalah salah satu
suku bangsa minoritas yang
hidup di Pulau Sumatera,
tepatnya di Provinsi Jambi dan
Sumatera Selatan. Mereka
mayoritas hidup di propinsi
Jambi, dengan perkiraan jumlah
populasi sekitar 200.000 orang.
Mereka hidup secara nomaden dan mendasarkan hidupnya pada berburu dan
meramu, walaupun banyak dari mereka sekarang telah memiliki lahan karet
dan pertanian lainnya. Suku Kubu di Jambi pada umumnya bermukim di
daerah pedesaan dengan pola yang mengelompok.
Gambar 3.8. Pemukiman penduduk suku Baduy
Gambar 3.9. Pemukiman penduduk suku Kubu

17
d. Suku Dayak
Dayak atau Daya adalah suku-
suku asli yang mendiami Pulau
Kalimantan, lebih tepat lagi
adalah yang memiliki budaya
terrestrial (daratan, bukan
budaya maritim). Sebutan ini
adalah sebutan umum karena
orang Daya terdiri dari beragam
budaya dan bahasa. Suku Dayak
diperkirakan mulai datang ke pulau Kalimantan pada tahun 3000-1500
Sebelum Masehi. Mereka adalah kelompok-kelompok yang bermigrasi dari
daerah Yunnan, Cina Selatan. Kelompok ini disebut Proto-Melayu. Rumah adat
suku dayak dikenal dengan nama “Rumah Betang”.
Gambar 3.11. Peta Persebaran Beberapa Suku Terasing di Indonesia
D. Bentuk Pola Pemukiman Penduduk
Pola persebaran pemukiman penduduk dipengaruhi oleh keadaan iklim,
keadaan tanah, tata air, topografi dan ketersediaan sumber daya alam yang
terdapat di wilayah tersebut.
Gambar 3.10. Rumah adat suku dayak

18
Ada tiga pola pemukiman penduduk dalam hubungannya dengan bentang
alamnya, yaitu sebagai berikut:
1. Pola Pemukiman Memanjang (Linear)
Pola pemukiman memanjang memiliki ciri pemukiman berupa deretan
memanjang karena mengikuti jalan, sungai, rel kereta api atau pantai.
Gambar 3.12. Pemukiman penduduk memanjang
a. Mengikuti jalan
Pada daerah ini pemukiman
berada di sebelah kanan kiri jalan.
Umumnya pola pemukiman
seperti ini banyak terdapat di
dataran rendah yang
morfologinya landai sehingga
memudahkan pembangunan
jalan-jalan di pemukiman. Namun
pola ini sebenarnya terbentuk
secara alami untuk mendekati
sarana transportasi.
Gambar 3.13. Pola pemukiman mengikuti jalan

19
b. Mengikuti rel kereta api
Pada daerah ini pemukiman
berada di sebelah kanan kiri rel
kereta api. Umumnya pola
pemukiman seperti ini banyak
terdapat di daerah perkotaan
terutama di DKI Jakarta dan atau
daerah padat penduduknya yang
dilalui rel kereta api.
c. Mengikuti alur sungai
Pada daerah ini pemukiman
terbentuk memanjang mengikuti
aliran sungai. Biasanya pola
pemukiman ini terdapat di daerah
pedalaman yang memiliki sungai-
sungai besar. Sungai-sungai
tersebut memiliki fungsi yang
sangat penting bagi kehidupan
penduduk.
Gambar 3.14. Pola pemukiman mengikuti jalan atau rel kereta api
Gambar 3.15. Pola pemukiman mengikuti alur sungai

20
d. Mengikuti garis pantai
Daerah pantai pada umumnya
merupakan pemukiman penduduk
yang bermata pencaharian
nelayan. Pada daerah ini
pemukiman terbentuk memanjang
mengikuti garis pantai. Hal itu
untuk memudahkan penduduk
dalam melakukan kegiatan
ekonomi yaitu mencari ikan ke
laut.
2. Pola Pemukiman Terpusat
Pola pemukiman ini
mengelompok membentuk unit-
unit yang kecil dan menyebar,
umumnya terdapat di daerah
pegunungan atau daerah dataran
tinggi yang berelief kasar, dan
terkadang daerahnya terisolir.
Di daerah pegunungan pola
pemukiman memusat mengitari
mata air dan tanah yang subur. Sedangkan daerah pertambangan di pedalaman
pemukiman memusat mendekati lokasi pertambangan. Penduduk yang tinggal
di pemukiman terpusat biasanya masih memiliki hubungan kekerabatan dan
hubungan dalam pekerjaan. Pola pemukiman ini sengaja dibuat untuk
mempermudah komunikasi antarkeluarga atau antarteman bekerja.
Gambar 3.17. Pemukiman terpusat di daerah pegunungan
Gambar 3.16. Pola pemukiman mengikuti garis pantai

21
3. Pola Pemukiman Tersebar.
Pola pemukiman tersebar terdapat di daerah dataran tinggi atau daerah
gunung api dan daerah-daerah yang kurang subur. Pada daerah dataran tinggi
atau daerah gunung api penduduk akan mendirikan pemukiman secara tersebar
karena mencari daerah yang tidak terjal, morfologinya rata dan relatif aman.
Sedangkan pada daerah kapur pemukiman penduduk akan tersebar mencari
daerah yang memiliki kondisi air yang baik. Mata pencaharian penduduk pada
pola pemukiman ini sebagian besar dalam bidang pertanian, ladang, perkebunan
dan peternakan.
Gambar 3.18. Pola Pemukiman Tersebar

22
BAB IV INTERPRETASI PETA
A. Definisi Interpretasi Peta
Gambar 4.1. Peta Indonesia
Pada masa sekarang, peta sebagai sarana informasi sudah merupakan
suatu kebutuhan. Tidak hanya orang-orang yang bekerja pada bidang tertentu
saja yang harus mengerti peta, namun juga masyarakat awam.
Membaca peta berarti mempelajari penampakan geografis yang
ditunjukkan oleh berbagai simbol dalam peta. Oleh karena itu jika seseorang
ingin memahami dan membaca sebuah peta, terlebih dahulu ia harus mengenal
berbagai unsur dalam peta terutama simbol-simbol. Seorang pembaca peta

23
harus menganalisis simbol-simbol dalam peta, kemudian memberikan
interpretasi atau penafsiran tentang penampakan geografis yang ada. Dengan
demikian yang dimaksud dengan interpretasi peta adalah kegiatan membaca
peta dengan memberikan penafsiran atau memaknai isi peta atas dasar simbol-
simbol yang ada.
B. Fungsi Interpretasi Peta
Dalam membaca peta, kita harus memahami dengan baik semua simbol
atau informasi yang ada pada peta. Kalau Anda dapat membaca peta dengan baik
dan benar, maka Anda akan memiliki gambaran mengenai keadaan wilayah yang
ada dalam peta, walaupun belum pernah melihat atau mengenal medan (muka
bumi) yang bersangkutan secara langsung. Seorang pembaca peta harus
menganalisis simbol-simbol dalam peta, kemudian memberikan interpretasi
atau penafsiran tentang penampakan geografis yang ada.
Membaca dan menafsirkan peta merupakan dua kegiatan yang saling
berkaitan satu sama lainnya. Jika kita telah membaca dan memahami peta
dengan baik, maka kita akan mendapatkan fungsi interpretasi peta sebagai
berikut:
1. Mengetahui berbagi objek geografi seperti gunung, pegunungan, sungai,
danau, dataran rendah, dataran tinggi, laut, jalan, jalan kereta api dll.
2. Mengetahui daerah yang jarang dan yang padat penduduknya
3. Mengetahui persebaran barang tambang.
4. Mengetahui obyek-obyek wisata.
5. Mengetahui potensi suatu daerah.
6. Mengetahui jarak lurus antarkota
7. Mengetahui keadaan suatu wilayah, misalnya untuk kepentingan
perhubungan
8. Mengetahui keadaan sosial budaya penduduk, misalnya mata pencaharian,
persebaran sarana kota dan persebaran pemukiman.

24
Gambar 4.2. Interpretasi data
C. Objek Geografi Alami
Peta merupakan media untuk menyimpan dan menyajikan informasi
tentang permukaan bumi dengan penyajian pada skala tertentu. Gambar unsur
permukaan bumi pada peta tidak selalu dapat disajikan sesuai ukurannya
karena terlalu kecil untuk digambarkan. Bila unsur itu dianggap penting untuk
disajikan, maka penyajiannya menggunakan simbol-simbol gambar tertentu.
Simbol-simbol yang ada pada peta digunakan untuk membedakan berbagai
obyek, salah satunya objek geografi alami. Yang termasuk kedalam objek
geografi alami antara lain kenampakan-kenampakan di permukaan bumi
seperti:
1. Dataran Rendah (Warna hijau)
Dataran rendah adalah tanah yang keadaannya relatif datar dan luas
sampai ketinggian sekitar 200 m dari permukaan laut. Dataran ini biasanya
ditemukan di sekitar pantai, tetapi ada juga yang terletak di pedalaman. Pada

25
peta dilambangkan dengan simbol warna hijau. Dataran ini biasanya tanahnya
subur, sehingga penduduknya lebih padat bila dibandingkan dengan daerah
pegunungan. Di Indonesia banyak dijumpai dataran rendah, misalnya pantai
timur Sumatera, pantai utara Jawa Barat, pantai selatan Kalimantan, Irian Jaya
bagian barat, dan lain-lain.
2. Dataran Tinggi (Warna Kuning)
Dataran Tinggi adalah daerah datar yang terletak di antara gunung atau
pegunungan, atau daerah yang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Dataran
tinggi pada peta umum dilambangkan dengan simbol warna kuning. Dataran
tinggi dinamakan juga plato (plateau), misalnya Dataran Tinggi Dekkan, Dataran
Tinggi Gayo, Dataran Tinggi Dieng, Dataran Tinggi Malang, atau Dataran Tinggi
Alas. Daerah ini sangat cocok untuk kegiatan pertanian sayuran dan buah-
buahan.
3. Pegunungan (Warna coklat keemasan)
Pegunungan merupakan suatu jalur memanjang yang berhubungan
antara puncak yang satu dengan puncak lainnya, misalnya Pegunungan Yura di
Prancis dan Pegunungan Panini di Inggris. Di Indonesia juga banyak ditemukan
pegunungan. Beberapa pegunungan di Indonesia seperti Pegunungan Bukit
Barisan di Sumatera, Pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan dan
Pegunungan Jaya Wijaya di Papua. Pegunungan pada peta umum dilambangkan
dengan simbol warna coklat.
4. Gunung
Gunung adalah bentuk muka bumi yang berbentuk kerucut atau kubah
yang berdiri sendiri. Bentuk gunung menjulang tinggi, yang berguna sebagai
penahan awan. Akibatnya daerah yang ada di daerah bawah dan sekitar gunung
bisa sering terjadi hujan. Adanya hujan ini bisa menjadikan hutan. Hutan dapat
berfungsi menyimpan air, akibatnya di sekitar hutan sering ditemukan mata air

26
dan sungai-sungai yang sangat bermanfaat bagi kehidupan mahluk hidup.
Gunung ada yang masih aktif dan ada juga gunung yang sudah tidak aktif lagi.
Gunung yang masih aktif dinamakan gunung berapi, Indonesia merupakan salah
satu negara yang memiliki gunung api yang sangat banyak. Gunung pada peta
umum dilambangkan dengan simbol segitiga, warna merah untuk gunung api
aktif sedangkan warna hitam gunung tidak aktif.
5. Sungai
Sungai merupakan tempat mengalirnya air dari daerah yang tinggi ke
tempat yang lebih rendah yang kemudian mengalir ke laut. Manfaat terbesar
sebuah sungai adalah sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah,
serta untuk keperluan rumah tangga, bahkan sebenarnya potensial untuk
dijadikan objek wisata sungai. Sungai pada peta umum dilambangkan dengan
simbol garis berwarna biru.
6. Danau
Danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh
air bisa tawar ataupun asin yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh
daratan. Sumber iar danau dapat terjadi karena mencairnya gletser, aliran
sungai, atau karena adanya mata air. Biasanya danau dapat dipakai sebagai
sarana rekreasi, dan olahraga. Pada peta danau digambarkan dengan simbol
area atau luasan berwarna biru muda
7. Laut (warna biru muda dan biru tua)
Laut merupakan kumpulan air asin yang luas dan berhubungan dengan
samudera. Samudra atau Lautan adalah yang luas dan merupakan massa air asin
yang sambung- menyambung meliputi permukaan bumi yang dibatasi oleh
benua ataupun kepulauan yang besar. Laut dan samudera memiliki potensi
sebagai pengahasil ikan, barang tambang, sarana transportasi dan sebagai batas
alam suatu negara atau wilayah. Laut pada pet umum digambarkan dengan

27
simbol bewarna biru, biru muda untuk laut dangkal dan biru tua untu laut
dalam.
Gambar 4.3. Objek geografi alami
D. Objek Geografi Buatan
Kenampakan permukaan bumi sebagai objek pada peta yang
digambarkan dengan simbol tidak hanya objek geografi alami tetapi simbol-
simbol pada peta juga kenampakan permukaan bumi yang dibuat oleh manusia
yang disebut objek geografi buatan. Yang termasuk kedalam objek geografi
buatan antara lain kenampakan-kenampakan di permukaan bumi seperti:
1. Kota dan Ibukota
Kota adalah wilayah administratif yang merupakan kawasan tempat
tinggal penduduk dengan bermacam-macam aktivitasnya , baik sosial, ekonomi,
maupun pemerintahan yang didukung oleh adanya sarana yang memadai seperti
jaringan jalan, pusat-pusat perdagangan dan berbagai fasilitas sosial lainnya.
Kota pada peta umum digambarkan dengan simbol garis titik, dan ibukota pada
peta umum digambarkan dengan simbol titik berupa segi empat berwarna
merah.

28
2. Jalan
Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian
jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan
bagi lalu lintas, yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain.
Jalan pada peta umum digambarkan dengan simbol garis berwarna merah.
3. Jalan Kereta Api
Jalan kereta api merupakan landasan kereta api yang terdiri dari rel
konvensional, maupun sistem monorel atau maglev. Kereta api merupakan
sarana transportasi yang paling murah karena dapat mengangkut pumpang
maupun barang dalam jumlah banyak dengan biaya rendah. Jalan kereta api
pada peta umum digambarkan dengan simbol garis putus hitam putih kotak-
kotak.
4. Waduk
Waduk adalah kolam besar tempat menyimpan persediaan air untuk
berbagai kebutuhan. Waduk dapat terjadi secara alami maupun dibuat manusia.
Waduk buatan dibangun dengan cara membendung aliran sungai. Waduk atau
bendungan memiliki banyak kegunaan seperti untuk PLTA. Objek wisata, olah
raga air, dan perikanandarat. Waduk pada peta umum digambarkan dengan
simbol area berwarna biru keputihan.
5. Pelabuhan Laut
Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan
disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan
dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar,
berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang

29
dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang
pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
6. Bandar Udara
Bandar udara atau bandara merupakan sebuah fasilitas tempat pesawat
terbang dapat lepas landas dan mendarat. Bandara yang paling sederhana
minimal memiliki sebuah landasan pacu namun bandara-bandara besar
biasanya dilengkapi berbagai fasilitas lain, baik untuk operator layanan
penerbangan maupun bagi penggunanya. Bandar Udara pada peta umum
digambarkan dengan simbol pesawat terbang berwarna merah
Gambar 4.4. Objek geografi buatan

30

31
BAB V
PETA, ATLAS, DAN GLOBE
A. Peta
Peta dapat diartikan gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi
yang diperkecil pada bidang datar
B. Jenis-Jenis Peta
Berdasarkan isinya ada dua (2) jenis peta yaitu: peta umum dan peta
khusus.
1. Peta Umum
Adalah peta yang menggambarkan kenampakan umum. Contoh Peta
Pulau Sulawesi
Gambar 5.1. Peta umum
2. Peta Khusus
Peta khusus atau peta tematik adalah peta yang menggambarkan satu
atau beberapa aspek saja dari gejala di permukaan bumi
Contohnya :

32
Gambar 5.2. Peta khusus
Berdasarkan objeknya ada dua (2) jenis peta yaitu: peta stasioner dan
peta dinamik.
1. Peta Stasioner
Peta Stasioner adalah peta yang menggambarkan obyek yang tetap
(tidak berubah).
Contohnya :
Gambar 5.3. Peta stasioner

33
2. Peta Dinamik
Peta dinamik adalah peta yang menggambarkan obyek yang relatif
mudah berubah. Contohnya : Peta jalur transportasi darat
Gambar 5.4. Peta dinamik
C. Bentuk-Bentuk Peta
1. Peta Planimetri
Peta Planimetri sering disebut juga peta dasar atau peta dua dimensi.
Peta Planimetri adalah peta yang dibuat pada bidang datar, seperti kertas atau
tripleks. Kenampakan permukaan bumi pada peta ini digambarkan dengan
menggunakan simbol-simbol tertentu misalnya dataran rendah digambarkan
dengan warna hijau, pegunungan dengan warna coklat dan perairan dengan
warna biru.

34
Gambar 5.5. Peta planimetri
2. Peta Setereometri
Peta Stereometri sering disebut juga peta timbul atau peta tiga dimensi.
Peta Stereometri dibuat berdasarkan bentuk bumi yang sesungguhnya. Peta
Peta Stereometri tinggi rendahnya bentuk permukaan bumi dapat kita lihat
dengan jelas. Pengamatan peta dilakukan dengan melihat dari atas.
3. Peta Digital
Peta digital merupakan peta hasil pengolahan data digital yang tersimpan
dalam komputer. Peta ini dapat disimpan dalam disket atau CD Rom. Contoh
Citra satelit, foto udara.
Gambar 5.6. Peta seteredmetri

35
D. Pemanfaatan Peta
1. Dasar Perencanaan dan Pembangunan
Informasi geografis yang ada dalam peta dapat digunakan sebagai dasar
perencanaan dan pengambilan keputusan. Misalnya perencanaan pembangunan
jalan, pusat perdagangan, perjalanan wisata dll. Dalam bidang militer, peta
digunakan untuk membantu menentukan lokasi persembunyian musuh
sehingga memudahkan penyerangan. Dalam bidang sosial budaya, peta
digunakan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan.
2. Menunjukkan Lokasi Suatu Wilayah
Peta dapat digunakan untuk mengetahui lokasi suatu tempat.
Misalnya wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia, sehingga dapat
membantu untuk mencapai tempat yang dituju.
3. Sebagai Sumber Informasi
Peta merupakan sumber informasi yang penting. Di dalam peta terdapat
informasi geografis, baik fisik maupun sosial, seperti iklim, penduduk, potensi
kekayaan alam, tingkat kemiskinan, jalan, lokasi pertambangan, dll.
Gambar 5.7. Peta digital

36
Peta juga memberikan informasi tentang perubahan suatu gejala geografis dari
waktu ke waktu, misalnya perubahan luas hutan dari tahun 1980 – 2000,
perubahan tata guna lahan pasca Tsunami di Aceh dan sebagainya.
a. Informasi Geografis Dari Peta
Informasi yang dapat dibaca dalam peta, antara lain :
1) Kenampakan Umum
Pada saat menggunakan peta, kita akan melihat kenampakan
suatu objek di permukaan bumi, seperti sungai, gunung, danau, dan kota.
2) Jarak
Jarak suatu tempat dengan tempat lain dapat diketahui dengan
menggunakan peta. Jarak yang dihitung dengan menggunakan peta
dilakukan dengan cara menarik garis lurus, untuk mengetahui jarak
sebenarnya di lapangan sesuai dengan skala peta yang bersangkutan.
3) Arah
Pembacaan arah pada peta secara sederhana dapat ditentukan
dengan pedoman pada tanda orientasi arah utara di dalam peta.
Dengan mengetahui arah utara, maka arah lain dapat ditentukan.
Gambar 5.8. Kenampakan Umum

37
4) Lokasi
Peta yang baik selalu mencantumkan jaring-jaring derajat yang
terdiri dari garis lintang dan garis bujur. Dengan melihat peta maka kita
dapat menentukan lokasi suatu tempat di permukaan bumi.
5) Ketinggian
Peta dapat menginformasikan kepada pembacanya tentang tinggi
rendahnya suatu tempat. Ketinggian suatu tempat dapat ditunjukkan
dengan tiga cara, yaitu titik ketinggian, garis kontur dan pewarnaan.
Gambar 5.9. Pembacaan arah
Gambar 5.10. Peta lokasi

38
E. ATLAS
Atlas merupakan kumpulan peta yang dibukukan. Atlas dapat
menginformasikan kenampakan umum, lokasi, jarak, arah dan ketinggian
tempat.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan atlas :
1. Memperhatikan simbol-simbol yang ada dalam legenda dan peta.
2. Gunakan indeks dan daftar isi untuk mempermudah mencari dan menemukan
nama-nama unsur geografis.
Gambar 5.11. Peta ketinggian tempat
Gambar 5.12. Atlas

39
F. Globe
Globe adalah gambaran permukaan bumi pada sebuah tiruan bola bumi.
Informasi geografis yang didapatkan dari globe, antara lain :
1. Menunjukkan bentuk bumi yang sesungguhnya.
2. Menirukan rotasi bumi.
3. menunjukkan garis lintang dan garis bujur.
4. Menunjukkan kemiringan sumbu bumi.
G. Skala
Skala adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak
sesungguhnya. Berdasarkan penulisannya ada 3 jenis skala, yaitu:
1. Skala Angka
Skala angka adalah skala yang menunjukkan perbandingan antara jarak
di peta dan jarak sebenarnya dengan angka. Contoh skala angka 1:50.000. Skala
angka 1:50.000, artinya jarak satu satuan yang tergambar pada peta sama
dengan 50.000 satuan di permukaan bumi. Berarti 1 cm di peta mewakili 50.000
cm jarak di lapangan. Jika ada 2 buah kota, yaitu kota A dan B pada sebuah peta
Gambar 5.13. Globe

40
yang berskala 1:50.000 adalah 20 cm maka jarak sesungguhnya antara kota A
dan B adalah :
=
=
=
20 cm x 50.000
1.000.000 cm
10 km
2. Skala Verbal
Skala Verbal adalah skala yang dinyatakan dengan kalimat atau secara
verbal. Skala ini sering terdapat pada peta-peta yang tidak menggunakan satuan
pengukuran matrik, seperti peta-peta di Inggris. Contoh skala verbal adalah 1
inchi to 1 mile, artinya 1 inchi pada peta menyatakan jarak 1 mil di lapangan.
Apabila 1 mil = 63.360 inchi, maka skala tersebut bila dinyatakan dalam skala
angka menjadi 1 : 63.360
3. Skala Grafik
Skala Grafik ditunjukkan oleh garis lurus yang dibagi dalam beberapa
ruas, dan setiap ruas menunjukkan satuan panjang yang sama. Contoh skala
grafik.
Gambar 5.14. Skala angka

41
BAB VI
HAKEKAT LINGKUNGAN HIDUP
A. Pengertian Lingkungan Hidup
Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya. Baik
lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Kita bernapas memerlukan udara
dari lingkungan sekitar. Kita makan, minum, menjaga kesehatan, semuanya
memerlukan lingkungan.
Pengertian lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia
yang memengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun
tidak langsung. Lingkungan bisa dibedakan menjadi lingkungan biotik dan
abiotik. Jika kalian berada di sekolah, lingkungan biotiknya berupa teman-teman
sekolah, bapak ibu guru serta karyawan, dan semua orang yang ada di sekolah,
juga berbagai jenis tumbuhan yang ada di kebun sekolah serta hewan-hewan
yang ada di sekitarnya. Adapun lingkungan abiotik berupa udara, meja kursi,
papan tulis, gedung sekolah, dan berbagai macam benda mati yang ada di
sekitar.
Definisi lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda,
daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan
perilakunya. Pendapat lain tentang lingkungan hidup adalah kesatuan ruang
dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup termasuk di dalamnya
manusia dan perilakunya yang melangsungkan perikehidupan dan
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
B. Unsur-Unsur Lingkungan Hidup
Unsur-unsur lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:
1. Unsur Hayati (Biotik)
Unsur hayati (biotik), yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari
makhluk hidup, seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan jasad renik.

42
Jika kalian berada di kebun sekolah, maka lingkungan hayatinya didominasi
oleh tumbuhan. Tetapi jika berada di dalam kelas, maka lingkungan hayati
yang dominan adalah teman-teman atau sesama manusia.
Menurut fungsinya, komponen biotik dapat dibedakan menjadi tiga
(3) kelompok utama yaitu:
a. Kelompok produsen
Kelompok produsen adalah organisme yang mampu menghasilkan
makanannya sendiri, yang biasa disebut dengan autotrofik (auto= sendiri,
trofik= menghasilkan makanan). Organisme tersebut mengubah bahan-
bahan organik menjadi bahan anorganik dengan bantuan energi matahari
dalam butir-butir hijau daun atau klorofil. Pada klorofil itulah proses
fotosintesis berlangsung, yang termasuk kelompok produsen adalah
tumbuh-tumbuhan yang berhijau daun (klorofil).
b. Kelompok konsumen
Kelompok konsumen adalah organisme yang hanya memanfaatkan hasil
yang disediakan oleh organisme lain (produsen). Oleh karena itu,
konsumen disebut dengan heterotrofik. Kelompok ini terdiri atas manusia
dan kelompok hewan herbivora (pemakan tumbuh-tumbuhan). Hewan
herbivora selanjutnya dimakan oleh binatang karnivora (pemakan hewan
lainnya), dan kedua jenis binatang ini dimakan oleh manusia, yang
termasuk dalam golongan omnivora (pema¬kan segalanya).
c. Kelompok pengurai (Decomposer)
Kelompok pengurai berperan dalam menguraikan sisa-sisa atau makhluk
hidup yang telah mati. Termasuk dalam kelompok pengurai adalah
bakteri dan jamur. Hasil penguraiannya berupa mineral-mineral dan air
yang kembali ke tanah, serta gas-gas yang terlepas kembali ke atmosfer

43
2. Unsur Sosial Budaya
Unsur sosial budaya, yaitu lingkungan sosial dan budaya yang dibuat
manusia yang merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam perilaku
sebagai makhluk sosial. Kehidupan masyarakat dapat mencapai keteraturan
berkat adanya sistem nilai dan norma yang diakui dan ditaati oleh segenap
anggota masyarakat.
3. Unsur Fisik (Abiotik)
Unsur fisik (abiotik), yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari
benda-benda tidak hidup, seperti tanah, air, udara, iklim, dan lain-lain.
Keberadaan lingkungan fisik sangat besar peranannya bagi kelangsungan
hidup segenap kehidupan di bumi. Bayangkan, apa yang terjadi jika air tak
ada lagi di muka bumi atau udara yang dipenuhi asap? Tentu saja kehidupan
di muka bumi tidak akan berlangsung secara wajar. Akan terjadi bencana
kekeringan, banyak hewan dan tumbuhan mati, perubahan musim yang tidak
teratur, munculnya berbagai penyakit, dan lain-lain.
Berikut termasuk dalam kelompok abiotik.
a. Tanah
Tanah merupakan tubuh alam yang berfungsi sebagai tempat tinggal
makhluk hidup dengan segala aktivitasnya. Selain berperan sebagai tempat
tinggal makhluk hidup, tanah juga menyediakan unsur-unsur yang
diperlukan untuk kehidupan tumbuhan seperti unsur hara, bahan organik,
serta air yang terdapat di dalam tanah.
b. Atmosfer (lapisan udara)
Atmosfer merupakan lapisan udara yang menyelimuti bumi. Dalam
atmosfer terdapat berbagai gas yang sangat penting bagi kehidupan
makhluk hidup di bumi. Salah satu gas yang mempunyai peranan sangat
penting bagi makhluk hidup adalah oksigen yang digunakan manusia dan
hewan untuk bernapas. Manusia dan hewan bernapas menghirup oksigen

44
dan mengeluarkan gas karbon dioksida, dan sebaliknya tumbuhan
menyerap karbon dioskida dan membuang oksigen ke udara.
c. Air
Air merupakan sumber utama kehidupan, karena tanpa adanya air
makhluk hidup tidak akan bisa hidup. Lebih dari 70% permukaan bumi
terdiri atas air, namun dari sekian besar volume air yang terdapat di bumi,
hanya sebagian kecil saja yang dapat digunakan (air segar).
d. Sinar Matahari
Sinar matahari merupakan sumber energi utama bagi kehidupan. Pada
tumbuhan, sinar matahari berguna untuk proses fotosintesis.
Lingkungan hidup baik faktor biotik maupun abiotik berpengaruh dan
dipengaruhi manusia. Segala yang ada pada lingkungan dapat dimanfaatkan oleh
manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, karena lingkungan
memiliki daya dukung. Daya dukung lingkungannya adalah kemampuan
lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup
lainnya.
Dalam kondisi alami, lingkungan dengan segala keragaman interaksi yang
ada mampu untuk menyeimbangkan keadaannya. Namun tidak tertutup
kemungkinan, kondisi demikian dapat berubah oleh campur tangan manusia
dengan segala aktivitas pemenuhan kebutuhan yang terkadang melampaui
batas. Keseimbangan lingkungan secara alami dapat berlangsung karena
beberapa hal, yaitu komponen-komponen yang ada terlibat dalam aksi-reaksi
dan berperan sesuai kondisi keseimbangan, pemindahan energi (arus energi),
dan siklus biogeokimia dapat berlangsung. Keseimbangan lingkungan dapat
terganggu bila terjadi perubahan berupa pengurangan fungsi dari komponen
atau hilangnya sebagian komponen yang dapat menyebabkan putusnya mata

45
rantai dalam ekosistem. Salah satu faktor penyebab gangguan adalah polusi di
samping faktor-faktor yang lain.
Komponen-komponen lingkungan hidup yang berada di sekitar kita
merupakan satu kesatuan yang saling memengaruhi antara komponen yang satu
dengan komponen yang lain disebut dengan ekosistem. Ekosistem dapat
dibedakan sebagai berikut,
a. Ekosistem darat terdiri dari: pegunungan, padang rumput, gurun pasir, hutan.
b. Ekosistem Perairan terdiri dari: kolam, telaga, rawa, sungai, dan laut
Hubungan antar komponen ini tidak hanya terjadi antarindividu, tetapi
juga adanya interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. llmu yang
mempelajari tentang hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik
di dalam ekosistem disebut dengan ekologi.
C. Pemanfaatan Lingkungan Hidup
Manusia merupakan salah satu makhluk yang selalu berinteraksi dengan
alam lingkungannya. Manusia memengaruhi lingkungan hidupnya karena
manusia mengusahakan dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di
lingkungannya untuk keperluan hidup. Majunya peradaban dan bertambahnya
jumlah populasi manusia menyebab¬kan kebutuhan akan sumber daya juga
semakin meningkat.
Pemanfaatan sumber daya alam yang ada harus dilakukan secara
bijaksana, artinya harus memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan dari
adanya eksploitasi yang berlebihan. Misalnya, eksploitasi terhadap sumber daya
alam biotik, meskipun dapat diperbarui jika penggunaannya tidak bijaksana
lama kelamaan akan rusak bahkan habis. Pemanfaatan sumber daya alam
dengan bijaksana itu sangat penting, mengingat bahwa: 1) Adanya keterbatasan
dari sumber daya alam; 2) Persebaran sumber daya alam yang tidak merata ; 3)
Sifat dari sumber daya alam, yaitu dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui.

46
Dengan adanya faktor-faktor di atas, maka cara pemanfaatan sumber
daya alam yang tersedia harus memerhatikan hal-hal sebagai berikut,
1. Selektif, artinya pemanfaatan sumber daya alam harus benar-benar diseleksi
dan diusahakan apabila benar-benar diperlukan.
2. Tidak boros, artinya memperhitungkan efisiensi dalam hal penggunaan, agar
tetap terjaga kelestariannya.
3. Mengusahakan agar tidak terjadi pencemaran. Hal ini harus dilakukan agar
sumber daya alam yang ada dapat digunakan untuk kesejahteraan hidup
manusia.
4. Dilakukan kegiatan pembaharuan dalam rangka pengawetan. Hal ini perlu
diupayakan untuk mencegah terjadinya kelangkaan sumber daya alam jenis

47
BAB VII
HUTAN DAN PEMANFAATANNYA
A. Definisi Hutan
Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar dan
beragam. Salah satu keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia adalah
hutan yang tersebar di sebagian besar pulau-pulau yang ada di Indonesia. Jenis
hutan apa yang ada di daerahmu? Mari kita pelajari materi ini.
Hutan merupakan salah satu bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh
dunia. Kita dapat menemukan hutan baik di daerah tropis maupun daerah
beriklim dingin, di dataran rendah maupun di pegunungan, di pulau kecil
maupun di benua besar. Orang awam mungkin melihat hutan lebih sebagai
sekumpulan pohon kehijauan dengan beraneka jenis satwa dan tumbuhan liar.
Untuk sebagian, hutan berkesan gelap, tak beraturan, dan jauh dari pusat
peradaban. Sebagian lain bahkan akan menganggapnya menakutkan.

48
Namun, jika kita mengikuti pengertian ilmu kehutanan, Hutan adalah
sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan
lainnya, yang menempati daerah yang cukup luas. Usaha pengelolaan dan
pemanfaatan hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia disebut
kegiatan kehutanan.
Wilayah Indonesia terdiri atas
sekita 17.000 pulau besar dan
kecil membentang sepanjang
garis khatulistiwa. Jumlah
tersebut menjadikan Indonesia
sebagai negara kepulauan
terbesar di dunia. Kondisi
geografis tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki
keragaman flora dan fauna yang sangat melimpah. Indonesia juga diakui sebagai
negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Indonesia
memiliki habitat yang sangat luas meliputi rawa, hutan basah dan kering,
padang rumput, serta gunung bersalju. Oleh karena itu jenis tumbuhan di
Indonesia sangat beragam.
Wilayah Indonesia yang berada di khatulistiwa selalu mendapat sinar
Matahari yang banyak sepanjang tahun, suhu udara yang relatif sedang sampai
tinggi, dan curah hujan yang juga tinggi. Kondisi ini memungkinkan tumbuhnya
berbagai jenis tanaman dari mulai lumut hingga pohon yang tingginya mencapai
50 meter.
B. Faktor Yang Mempengaruhi Persebaran Hutan
Adanya perbedaan jenis tumbuhan di permukaan bumi dipengaruhi oleh
faktor-faktor tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran hutan
antara lain:

49
1. Iklim
Iklim dengan unsur-unsurnya, seperti suhu udara, tekanan udara,
kelambapan udara, angin dan curah hujan merupakan faktor utama yang
mempengaruhi perseberan tumbuhan (flora) di permukaan bumi. Hutan hujan
tropis merupakan hutan yang banyak dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi.
2. Keadaan Tanah
Perbedaaan jenis tanah, seperti
pasir, aluvial, dan kapur serta
jumlah zat mineral yang
terkandung dalam humus
mempengaruhi jenis tanaman yang
tumbuh. Di daerah tropis akan
hidup berbagai jenis tumbuhan,
sedangkan di daerah gurun atau
bersalju hanya akan hidup tumbuhan tertentu. Tumbuhan kaktus salah satu
tumbuhan yang mampu beradaptasi dengan kondisi iklim dan keadaan tanah di
gurun pasir.
3. Tinggi Rendah Permukaan Bumi (Relief)
Permukaan bumi terdiri dari
berbagai macam relief , seperti
pegunungan, dataran rendah,
perbukitan dan daerah pantai.
Perbedaan tinggi-rendah
permukaan bumi mengakibatkan
variasi suhu udara. Variasi suhu
udara mempengaruhi keanekaragaman tumbuhan (flora). Hutan yang terdapat
di daerah pegunungan banyak dipengaruhi oleh ketinggian tempat.

50
4. Makhluk Hidup (Biotik)
Makhluk hidup seperti manusia
dan hewan memiliki pengaruh
yang cukup besar dalam
persebaran tumbuhan (flora).
Terutama manusia dengan ilmu
dan teknologi yang dimilikinya
dapat melakukan persebaran
tumbuhan dengan cepat dan mudah. Hutan kota merupakan jenis hutan yang
lebih banyak dipengaruhi oleh faktor biotik, terutama manusia.
C. Macam-macam Hutan
Banyak ilmuwan yang mengelompokkan hutan berdasarkan variasi
sistem ekologi. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam mengenali sifat
khas hutan. Dengan mengenali betul-betul sifat sebuah hutan, kita akan
memperlakukan hutan secara lebih tepat sehingga hutan dapat lestari, bahkan
terus berkembang. Ada berbagai macam hutan antara lain:
1. Berdasarkan Jenis Pohonnya
a. Hutan Heterogen adalah hutan yang terdiri atas berbagai jenis tumbuhan
seperti hutan hujan tropis yang terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan.
Sulawesi dan Papua.
b. Hutan homogen adalah hutan yang terdiri atas satu jenis pohon seperti
hutan jati, hutan bambu, hutan karet, dan hutan pinus.

51
2. Berdasarkan Tujuan Pemanfaatannya
a. Hutan produksi adalah hutan yang diusahakan melalui sistem Hak
Pengusahaan Hutan (HPH) baik BUMN maupun pengusaha swasta, yang
memanfaatkan hasil hutan seperti kayu untuk kegiatan produksi. Adapun
hasil dari kegiatan industri pengolahan kayu antara lain berupa triplek,
kusen pintu dan mebel serta perabot rumah tangga lainnya.
b. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok
sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata
air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan
memelihara kesuburan tanah.
c. Hutan wisata adalah hutan yang berfungsi untuk objek wisata sebagai
tempat rekreasi atau hiburan para wisatawan karena keindahan alamnya.
Kebun Raya Bogor merupakan salah satu hutan wisata yang banyak
dikunjungi wisatawan.

52
d. Hutan suaka alam adalah hutan yang memiliki keadaan alam khas,
diperuntukkan bagi perlindungan dan pelestarian flora dan fauna yang
hampir punah, agar dapat berkembang biak sesuai dengan kondisi
ekosistemnya. Hutan suaka alam Ujung Kulon merupakan tempat
perlindungan badak bercula satu dan beberapa fauna lainnya.
3. Berdasarkan Iklim Yang Mempengaruhinya
a. Hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis tumbuh di sekitar garis
khatulistiwa atau equator yang memiliki suhu udara dan curah hujan
yang tinggi sepanjang tahun. Sebagian besar hutan ini tumbuh di lembah
sungai Amazon, lembah sungai Kongo, dan di wilayah Asia Tenggara.
Hutan hujan tropis dikenal sebagai hutan heterogen karena terdiri dari
berbagai jenis tumbuhan. Di Indonesia hutan hujan tropis terdapat di
Pulau Sumatera, kalimantan dan Irian Jaya (Papua).

53
b. Hutan musim. Hutan musim terdapat di daerah di wilayah yang
mengalami perubahan musim hujan dan musim kemarau secara jelas.
Tumbuhan pada hutan musim umumnya bersifat homogen (satu jenis
tumbuhan), seperti hutan jati, hutan karet dan hutan bambu. Di Indonesia
hutan musim banyak terdapat di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.
c. Sabana dan Steppa. Sabana merupakan padang rumput yang diselingi
oleh pepohonan atau semak belukar, sedangkan steppa merupakan
padang rumput yang sangat luas. Sabana dan Steppa banyak dijumpai di
daerah bercurah hujan rendah atau relatif sedikit. Di Indonesia, sabana
dan steppa terdapat di Nusa Tenggara Barat dan Timur.
4. Berdasarkan Letak Geografisnya
a. Hutan Tropika
Secara astronomi hutan tropika terbentang pada wilayah 23,5oLU–
23,5oLS. Ciri-ciri utama kawasan ini adalah curah hujan yang cukup tinggi
dan Matahari bersinar sepanjang tahun. Curah hujan yang tinggi
menyebabkan hutan tropika sangat lebat yang terdiri dari berbagai jenis
pohon serta daunnya menghijau sepanjang tahun. Hutan ini berfungsi
sebagai paru-paru dunia karena kemampuannya dalam menyerap
karbondioksida serta menjaga keseimbangan suhu dan iklim dunia.

54
b. Hutan Temperate (Hutan gugur)
Hutan temperate atau hutan gugur terdapat di daerah beriklim sedang
yang memiliki empat musim, secara astronomis di antara 23,5o – 66,5o
lintang utara maupun lintang selatan. Hutan ini berisi tumbuhan yang
daunnya gugur (meranggas) pada musim dingin. Keadaan ini akan
berlangsung hingga menjelang musim semi. Pada musim semi,
temperatur akan meningkat, salju mulai mencair, tumbuhan mulai
berdaun kembali (bersemi). Daerah persebaran hutan gugur terutama
meliputi wilayah sub-tropis sampai sedang seperti Amerika Serikat,
Eropa Barat, Asia Tengah dan Timur serta Chili.

55
c. Hutan Boreal (Hutan Taiga)
Hutan boreal atau hutan taiga berkembang di daerah lintang tinggi dekat
dengan kawasan lingkar kutub dan merupakan jenis hutan terluas kedua
setelah hutan tropika. Hutan ini ditumbuhi oleh jenis pohon berdaun
jarum, dimana di kawasan ini memiliki musim panas yang pendek dan
musim dingin yang panjang. Daerah yang termasuk kawasan ini meliputi
Alaska-Amerika Utara, Skandinavia-Eropa Utara, dan Siberia-Rusia.
Vegetasi yang berkembang di daerah ini hanya satu jenis species saja
yaitu pohon spruce, alder, birch dan juniper. Permukaan tanah hutan ini
umumnya tertutup lumut kerak yang tebal.

56
5. Berdasarkan Ketinggian Tempat
a. Hutan Pantai (beach forest)
Hutan yang tumbuh di daerah pantai adalah hutan bakau (mangrove).
Hutan bakau memilik akar napas dan daun yang berlapis tebal di
pemukaannya untuk mengurangi penguapan. Hutan bakau banyak
dijumpai di pantai yang ombak lautnya tenang, seperti di pantai
Sumatera bagian Timur, pantai Kalimantan Barat, pantai Kalimantan
Selatan dan pantai Irian Jaya. Tumbuhan bakau memiliki karakteristik
khusus yang memungkinkan tumbuhan ini hidup dan beradaptasi dengan
lingkungannya. Lingkungan tempat hidup tanaman ini umumnya
memiliki kadar garam yang cukup tinggi, selalu tergenang, dan tanah
yang kurang oksigen.
b. Hutan Gambut
Hutan gambut merupakan suatu ekosistem lahan basah yang dibentuk
oleh adanya penimbunan atau akumulasi bahan organik di lantai hutan
yang berasal dari reruntuhan vegetasi di atasnya dalam kurun waktu
lama. Akumulasi ini terjadi karena lambatnya laju dekomposisi
dibandingkan dengan laju penimbunan bahan organik di lantai hutan
yang basah/tergenang tersebut.
Di Indonesia, lahan gambut terdapat di daerah pantai rendah Kalimantan,
Sumatera dan Papua Barat. Sebagian besar berada pada daerah rendah

57
dan tempat yang masih terpengaruh dengan kondisinya, berada di
daratan sampai jarak 100 km sepanjang aliran sungai dan daerah
tergenang.
c. Hutan Dataran Rendah (lowland forest)
Hutan dataran rendah merupakan hutan yang tumbuh di daerah dataran
rendah dengan ketinggian 0 - 1200 m. Hutan hujan tropis yang ada
wilayah Dangkalan Sunda seperti di Pulau Sumatera, dan Pulau
Kalimantan termasuk hutan dataran rendah.
Hutan dataran rendah Sumatera memiliki keanekaragaman hayati yang
terkaya di dunia. Sebanyak 425 jenis atau 2/3 dari 626 jenis burung yang
ada di Sumatera hidup di hutan dataran rendah bersama dengan harimau
Sumatera, gajah, tapir, beruang madu dan satwa lainnya. Selain itu, di
hutan dataran rendah Sumatera juga ditemukan bunga tertinggi di dunia
(Amorphophallus tittanum) dan bunga terbesar di dunia (Rafflesia
arnoldi).

58
d. Hutan Pegunungan Rendah (sub-mountaine forest)
Hutan ini terdapat di daerah Indonesia dengan ketinggian antara 1.300 m
sampai 2.500 m di atas permukaan laut. Hutan pegunungan memberikan
manfaat bagi masyarakat yang hidup di gunung maupun yang tinggal di
bawahnya. Hutan yang ada merupakan sumber kehidupan. Dari hutan
pegunungan, mereka memanfaatkan tumbuhan dan hewan sebagai
makanan, obat-obatan, kayu bakar, bahan bangunan dan lain sebagainya.
Selain itu masyarakat yang tinggal di bawahnya membutuhkan hutan
pegunungan yang lestari sebagai daerah tangkapan air atau resapan air.

59
e. Hutan Pegunungan Atas (mountaine forest)
Hutan ini terdapat di daerah daerah Indonesia dengan ketinggian di atas
3.500 m di atas permukaan laut. Hutan ini berfungsi sebagai cagar alam
dan taman wisata alam. Vegetasi hutan pegunungan yang dijadikan Cagar
Alam dan Taman Wisata Alam termasuk tipe hutan hujan tropik
pegunungan dengan floranya terdiri dari jenis-jenis pohon dan liana serta
epiphyte.
D. Manfaat Hutan
Hutan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan
sebagian besar rakyat Indonesia, karena hutan memberikan sumber kehidupan
bagi kita semua. Hutan menghasilkan air dan oksigen sebagai komponen yang
yang sangat diperlukan bagi kehidupan umat manusia. Demikian juga dengan
hasil hutan lainnya memberikan berbagai manfaat bagi kehidupan masyarakat.
Pengelolaan hutan bagi kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang
perlu menjadi perhatian bersama, baik oleh pemerintah, masyarakat maupun
dunia usaha. Pemanfaatan nilai ekonomis hutan bagi harus seimbang dengan
upaya pelestarian lingkungan hidup sehingga hutan tetap dapat dimanfaatkan
secara adil dan berkelanjutan. Adapun fungsi hutan antara lain:

60
1. Fungsi Ekonomi
a. Sebagai penghasil kayu dan hasil hutan lainnya seperti rotan, damar
dan lain-lain
b. Sebagai penghasil devisa bagi negara
2. Fungsi Ekologis
a. Mempertahankan kesuburan tanah
b. Mencegah terjadinya erosi
c. Mencegah terjadinya banjir
d. Sebagai tempat untuk mempertahankan keanekaragaman hayati
3. Fungsi Klimatologis
a. Sebagai penghasil oksigen
b. Sebagai pengatur iklim
4. Fungsi Hidrolis
a. Sebagai pengatur tata air tanah
b. Sebagi penyimpan air tanah
c. Mencegah intrusi air laut

61
BAB VIII PENCEMARAN LINGKUNGAN
A. Pendahuluan
Seiring dengan semakin meningkatnya populasi manusia dan bertambah
banyaknya kebutuhan manusia, mengakibatkan semakin besar pula terjadinya
masalah-masalah pencemaran lingkungan. Pada dasarnya, secara alamiah, alam
mampu mendaur ulang berbagai jenis limbah yang dihasilkan oleh makhluk
hidup, namun bila konsentrasi limbah yang dihasilkan sudah tak sebanding lagi
dengan laju proses daur ulang maka akan terjadi pencemaran.
Pencemaran lingkungan hidup yaitu; masuknya atau dimasukkannya
mahluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup,
oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu
yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan
peruntukkannya. Demikian pula dengan lingkungan air yang dapat pula
tercemar karena masuknya atau dimasukannya mahluk hidup atau zat yang
membahayakan bagi kesehatan. Air dikatakan tercemar apabila kualitasnya
turun sampai ke tingkat yang membahayakan sehingga air tidak bisa digunakan
sesuai peruntukannya.
B. Pencemaran Air
1. Pengertian Pencemaran Air
Air merupakan pelarut yang baik,
sehingga air di alam tidak pernah
murni akan tetapi selalu mengandung
berbagai zat terlarut maupun zat
tidak terlarut serta mengandung
mikroorganisme atau jasad renik.
Apabila kandungan berbagai zat

62
maupun mikroorganisme yang terdapat di dalam air melebihi ambang batas
yang diperbolehkan, kualitas air akan terganggu, sehingga tidak bisa digunakan
untuk berbagai keperluan baik untuk air minum, mandi, mencuci atau keperluan
lainya. Air yang terganggu kualitasnya ini dikatakan sebagai air yang tercemar.
Pencemaran air mengacu pada definisi lingkungan hidup yang ditetapkan
dalam UU tentang lingkungan hidup yaitu UU No. 23/1997. Dalam
PP No. 20/1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air, pencemaran air
didefinisikan sebagai : “pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya
mahluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiaan
manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang
menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya” (Pasal 1,
angka 2). Definisi pencemaran air tersebut dapat diuraikan sesuai makna
pokoknya menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu aspek kejadian, aspek penyebab atau
pelaku, dan aspek akibat (Setiawan, 2001).
Berdasarkan definisi pencemaran air, penyebab terjadinya pencemaran
dapat berupa masuknya mahluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam
air sehingga menyebabkan kualitas air tercemar. Masukan tersebut sering
disebut dengan istilah unsur pencemar, yang pada prakteknya masukan tersebut
berupa buangan yang bersifat rutin, misalnya buangan limbah cair. Aspek
pelaku/penyebab dapat yang disebabkan oleh alam, atau oleh manusia.
Pencemaran yang disebabkan oleh alam tidak dapat berimplikasi hukum,
tetapi Pemerintah tetap harus menanggulangi pencemaran tersebut. Sedangkan
aspek akibat dapat dilihat berdasarkan penurunan kualitas air sampai ke tingkat
tertentu. Pengertian tingkat tertentu dalam definisi tersebut adalah tingkat
kualitas air yang menjadi batas antara tingkat tak-cemar (tingkat kualitas air
belum sampai batas) dan tingkat cemar (kualitas air yang telah sampai ke batas
atau melewati batas). Parameter kualitas air minum/air bersih yang terdiri dari

63
parameter kimiawi, fisik, radioaktif dan mikrobiologi, ditetapkan dalam
PERMENKES 416/1990 (Achmadi, 2001).
C. Indikator Pencemaran Air
Indikator atau tanda bahwa air lingkungan telah tercemar adalah adanya
perubahan atau tanda yang dapat diamati yang dapat digolongkan menjadi:
1. Pengamatan secara fisis, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan
tingkat kejernihan air (kekeruhan), perubahan suhu, warna, dan adanya
perubahan warna, bau dan rasa.
2. Pengamatan secara kimiawi, yaitu pengamatan pencemaran air
berdasarkan zat kimia yang terlarut, dan perubahan pH.
3. Pengamatan secara biologis, yaitu pengamatan pencemaran air
berdasarkan mikroorganisme yang ada dalam air, terutama ada tidaknya
bakteri pathogen.
Indikator yang umum diketahui
pada pemeriksaan pencemaran air
adalah pH atau konsentrasi ion
hidrogen, oksigen terlarut
(Dissolved Oxygen, DO), kebutuhan
oksigen biokimia (Biochemiycal
Oxygen Demand, BOD) serta
kebutuhan oksigen kimiawi
Chemical Oxygen Demand, COD),
Jumlah total zat terlarut.
1. Oksigen terlarut (Dissolved Oxygen, DO)
Yang dimaksud adalah oksigen terlarut yang terkandung di dalam air,
berasal dari udara dan hasil proses fotosintesis tumbuhan air. Oksigen
diperlukan oleh semua mahluk yang hidup di air seperti ikan, udang, kerang dan

64
hewan lainnya termasuk mikroorganisme seperti bakteri. Agar ikan dapat hidup,
air harus mengandung oksigen paling sedikit 5 mg/ liter atau 5 ppm (part per
million). Apabila kadar oksigen kurang dari 5 ppm, ikan akan mati, tetapi bakteri
yang kebutuhan oksigen terlarutnya lebih rendah dari 5 ppm akan berkembang.
Apabila sungai menjadi tempat pembuangan limbah yang mengandung
bahan organik, sebagian besar oksigen terlarut digunakan bakteri aerob untuk
mengoksidasi karbon dan nitrogen dalam bahan organik menjadi
karbondioksida dan air. Sehingga kadar oksigen terlarut akan berkurang dengan
cepat dan akibatnya hewan-hewan seperti ikan, udang, dan kerang akan mati.
Lalu apakah penyebab bau busuk dari air yang tercemar? Bau busuk ini berasal
dari gas NH3 dan H2S yang merupakan hasil proses penguraian bahan organik
lanjutan oleh bakteri anaerob.
2. Kebutuhan oksigen biokimia (Biochemiycal Oxygen Demand, BOD)
BOD (Biochemical Oxygen Demand) artinya kebutuhan oksigen biokima
yang menunjukkan jumlah oksigen yang digunakan dalam reaksi oksidasi oleh
bakteri. Sehingga makin banyak bahan organik dalam air, makin besar B.O.D nya
sedangkan D.O akan makin rendah. Air yang bersih adalah yang B.O.D nya
kurang dari 1 mg/l atau 1ppm, jika B.O.D nya di atas 4ppm, air dikatakan
tercemar.
3. Kebutuhan oksigen kimiawi (Chemical Oxygen Demand, COD)
COD (Chemical Oxygen Demand) sama dengan BOD, yang menunjukkan
jumlah oksigen yang digunakan dalam reaksi kimia oleh bakteri. Pengujian COD
pada air limbah memiliki beberapa keunggulan dibandingkan pengujian BOD.
Keunggulan itu antara lain :
a. Sanggup menguji air limbah industri yang beracun yang tidak dapat diuji
dengan BOD karena bakteri akan mati.
b. Waktu pengujian yang lebih singkat, kurang lebih hanya 3 jam

65
Berdasarkan PP no 82 tahun 2001 pasal 8 tentang pengelolaan
lingkungan hidup, klasifikasi dan kriteria mutu air ditetapkan menjadi 4 kelas
yaitu:
Kelas 1 : yaitu air yang dapat digunakan untuk bahan baku air minum atau
peruntukan lainnya mempersyaratkan mutu air yang sama
Kelas 2 : air yang dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air,
budidaya ikan air tawar, peternakan, dan pertanian
Kelas 3 : air yang dapat digunakan untuk budidaya ikan air tawar, peternakan,
dan pertanian
Kelas 4 : air yang dapat digunakan untuk mengairi pertanaman/pertanian
D. Sumber-Sumber Pencemaran Air
1. Limbah Pemukiman
Limbah pemukiman mengandung
limbah domestik berupa sampah
organik dan sampah anorganik serta
deterjen. Sampah organik adalah
sampah yang dapat diuraikan atau
dibusukkan oleh bakteri. Contohnya
sisa-sisa sayuran, buah-buahan, dan
daun-daunan, sedangkan sampah
anorganik seperti kertas , plastik, gelas,
atau kaca, kain, kayu-kayuan, logam, karet, dan kulit. Sampah-sampah ini tidak
dapat diuraikan oleh bakteri (non biodegrable). Sampah organik yang dibuang ke
sungai menyebabkan berkurangnya jumlah oksigen terlarut, karena sebagian
besar digunakan bakteri untuk proses pembusukannya.
Apabila sampah anorganik yang dibuang ke sungai, cahaya matahari
dapat terhalang dan menghambat proses fotosintesis dari tumbuhan air dan
Gambar. Deterjen Hasil Cucian

66
alga, yang menghasilkan oksigen. Tentunya anda pernah melihat permukaan air
sungai atau danau yang ditutupi buih deterjen. Deterjen merupakan limbah
pemukiman yang paling potensial mencemari air. Pada saat ini hampir setiap
rumah tangga menggunakan deterjen, padahal limbah deterjen sangat sukar
diuraikan oleh bakteri. Sehingga tetap aktif untuk jangka waktu yang lama.
Penggunaan deterjen secara besar-besaran juga meningkatkan senyawa fosfat
pada air sungai atau danau. Fosfat ini merangsang pertumbuhan ganggang dan
eceng gondok. Pertumbuhan ganggang dan eceng gondok yang tidak terkendali
menyebabkan permukaan air danau atau sungai tertutup sehingga menghalangi
masuknya cahaya matahari dan mengakibatkan terhambatnya proses
fotosintesis. Jika tumbuhan air ini mati, akan terjadi proses pembusukan yang
menghabiskan persediaan oksigen dan pengendapan bahan-bahan yang
menyebabkan pendangkalan.
2. Limbah Pertanian
Pupuk dan pestisida biasa digunakan
para petani untuk merawat
tanamannya. Namun pemakaian pupuk
dan pestisida yang berlebihan dapat
mencemari air. Limbah pupuk
mengandung fosfat yang dapat
merangsang pertumbuhan gulma air
seperti ganggang dan eceng gondok.
Pertumbuhan gulma air yang tidak terkendali ini menimbulkan dampak seperti
yang diakibatkan pencemaran oleh deterjen.
Limbah pestisida mempunyai aktifitas dalam jangka waktu yang lama
dan ketika terbawa aliran air keluar dari daerah pertanian, dapat mematikan
hewan yang bukan sasaran seperti ikan, udang dan hewan air lainnya. Pestisida
Gambar . Pupuk dan Pestisida

67
mempunyai sifat relatif tidak larut dalam air, tetapi mudah larut dan cenderung
konsentrasinya meningkat dalam lemak dan sel-sel tubuh mahluk hidup disebut
Biological Amplification, sehingga apabila masuk dalam rantai makanan
konsentrasinya makin tinggi dan yang tertinggi adalah pada konsumen puncak.
Contohnya ketika di dalam tubuh ikan kadarnya 6 ppm, di dalam tubuh burung
pemakan ikan kadarnya naik menjadi 100 ppm dan akan meningkat terus
sampai konsumen puncak.
3. Limbah Industri
Limbah industri sangat potensial
sebagai penyebab terjadinya
pencemaran air. Pada umumnya
limbah industri mengandung limbah
B3, yaitu bahan berbahaya dan
beracun. Menurut PP 18 tahun 1999
pasal 1, limbah B3 adalah sisa suatu
usaha atau kegiatan yang mengandung
bahan berbahaya dan beracun yang
dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup sehingga membahayakan
kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk lainnya. Karakteristik
limbah B3 adalah korosif/ menyebabkan karat, mudah terbakar dan meledak,
bersifat toksik/beracun dan menyebabkan infeksi/ penyakit.
Limbah industri yang berbahaya antara lain yang mengandung logam dan
cairan asam. Misalnya limbah yang dihasilkan industri pelapisan logam, yang
mengandung tembaga dan nikel serta cairan asam sianida, asam borat, asam
kromat, asam nitrat dan asam fosfat. Limbah ini bersifat korosif, dapat
mematikan tumbuhan dan hewan air. Pada manusia menyebabkan iritasi pada
kulit dan mata, mengganggu pernafasan dan menyebabkan kanker.
Gambar . Limbah Industri

68
Logam yang paling berbahaya dari limbah industri adalah merkuri atau
yang dikenal juga sebagai air raksa (Hg) atau air perak. Limbah yang
mengandung merkurei selain berasal dari industri logam juga berasal dari
industri kosmetik, batu baterai, plastik dan sebagainya. Di Jepang antara tahun
1953- 1960, lebih dari 100 orang meninggal atau cacat karena mengkonsumsi
ikan yang berasal dari Teluk Minamata. Teluk ini tercemar merkuri yang
bearasal dari sebuah pabrik plastik. Senyawa merkuri yang terlarut dalam air
masuk melalui rantai makanan, yaitu mula-mula masuk ke dalam tubuh
mikroorganisme yang kemudian dimakan yang dikonsumsi manusia. Bila
merkuri masuk ke dalam tubuh manusia melalui saluran pencernaan, dapat
menyebabkan kerusakan akut pada ginjal sedangkan pada anak-anak dapat
menyebabkan Pink Disease/acrodynia, alergi kulit dan kawasaki disease/
mucocutaneous lymph node syndrome.
4. Limbah Pertambangan
Limbah pertambangan seperti batubara biasanya tercemar asam sulfat dan senyawa besi, yang dapat mengalir ke luar daerah pertambangan. Air yang mengandung kedua senyawa ini dapat berubah menjadi asam. Bila air yang bersifat asam ini melewati daerah batuan karang/kapur akan melarutkan senyawa Ca dan Mg dari batuan tersebut. Selanjutnya senyawa Ca dan Mg yang larut terbawa air akan memberi efek terjadinya AIR SADAH, yang tidak bisa digunakan untuk mencuci karena sabun tidak bisa
berbuih. Bila dipaksakan akan memboroskan sabun, karena sabun tidak akan
berbuih sebelum semua ion Ca dan Mg mengendap. Limbah pertambangan yang
bersifat asam bisa menyebabkan korosi dan melarutkan logam-logam sehingga
air yang dicemari bersifat racun dan dapat memusnahkan kehidupan akuatik.
Gambar . Limbah Pertambangan

69
Selain pertambangan batubara, pertambangan lain yang menghasilkan
limbah berbahaya adalah pertambangan emas. Pertambangan emas
menghasilkan limbah yang mengandung merkuri, yang banyak digunakan
penambang emas tradisional atau penambang emas tanpa izin, untuk
memproses bijih emas. Para penambang ini umumnya kurang mempedulikan
dampak limbah yang mengandung merkuri karena kurangnya pengetahuan yang
dimiliki. Biasanya mereka membuang dan mengalirkan limbah bekas proses
pengolahan pengolahan ke selokan, parit, kolam atau sungai. Merkuri tersebut
selanjutnya berubah menjadi metil merkuri karena proses alamiah. Bila
senyawa metil merkuri masuk ke dalam tubuh manusiamelalui media air, akan
menyebabkan keracunan seperti yang dialami para korban Tragedi Minamata.
E. Pencegahan Dampak Pencemaran Air
Limbah atau bahan buangan yang dihasilkan dari semua aktivitas kehidupan manusia, baik dari setiap rumah tangga, kegiatan pertanian, industri serta pertambangan tidak bisa kita hindari. Namun kita masih bisa mencegah atau paling tidak mengurangi dampak dari limbah tersebut, agar tidak merusak lingkungan yang pada akhirnya juga akan merugikan manusia. Untuk mencegah atau paling tidak mengurangi segala akibat yang
ditimbulkan oleh limbah berbahaya; setiap rumah tangga sebaiknya
menggunakan deterjen secukupnya dan memilah sampah organik dari sampah
anorganik. Sampah organik bisa dijadikan kompos, sedangkan sampah
anorganik bisa didaur ulang. Pemerintah bekerjasama dengan World Bank, pada
saat ini tengah mempersiapkan pemberian insentif berupa subsidi bagi
masyarakat yang melakukan pengomposan sampah kota.

70
Beberapa manfaat pengomposan sampah
antara lain :
Mengurangi sampah di sumbernya
Mengurangi beban volume di TPA
Mengurangi biaya pengelolaan
Menciptakan peluang kerja
Memperbaiki kondisi lingkungan
Mengurangi emisi gas rumah kaca
Penggunaan kompos mendukung; Produk
organik > Green Consumerism dan more
sustain land use.
Penggunaan pupuk dan pestisida secukupnya atau memilih pupuk dan
pestisida yang mengandung bahan-bahan yang lebih cepat terurai, yang tidak
terakumulasi pada rantai makanan, juga dapat megurangi dampak pencemaran
air.
Setiap pabrik/kegiatan industri sebaiknya memiliki Instalasi Pengolahan
Air Limbah (IPAL), untuk mengolah limbah yang dihasilkannya sebelum dibuang
ke lingkungan sekitar. Dengan demikian diharapkan dapat meminimalisasi
limbah yang dihasilkan atau mengubahnya menjadi limbah yang lebih ramah
lingkungan.
Mengurangi penggunaan bahan-bahan berbahaya dalam kegiatan
pertambangan atau menggantinya dengan bahan-bahan yang lebih ramah
lingkungan. Atau diharuskan membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah
pertambangan, sehingga limbah bisa diolah terlebih dahulu menjadi limbah yang
lebih ramah lingkungan, sebelum dibuang keluar daerah pertambangan.

71
F. Pencemaran Tanah
Penyebab terjadinya erosi tanah
Gambar : Kebakaran hutan, hutan gundul dan daerah longsor
Menurut kalian apakah tanah bisa mengalami kerusakan? dan faktor
apakah yang menyebabkannya? Tanah bisa mengalami kerusakan. Bahkan tanah
termasuk wujud alam yang mudah mengalami kerusakan. Salah satu contoh
kerusakan tanah adalah erosi tanah. Erosi tanah adalah tanah yang lapuk dan
mudah mengalami penghancuran.
Kerusakan yang dialami pada tanah tempat erosi disebabkan oleh
kemunduran sifat–sifat kimia dan fisik tanah, yakni:
1. Kehilangan unsur hara dan bahan organik,
2. Menurunnya kapasitas infiltrasi dan kemampuan tanah menahan air,
3. Meningkatnya kepadatan dan ketahanan penetrasi tanah,
4. Serta berkurangnya kemantapan struktur tanah yang pada akhirnya
menyebabkan memburuknya pertumbuhan tanaman dan menurunnya
produktivitas
Hal ini dikarenakan lapisan atas tanah setebal 15 sampai 30 cm
mempunyai sifat– sifat kimia dan fisik lebih baik dibandingkan lapisan lebih
bawah.

72
Banyaknya unsur hara yang hilang bergantung pada besarnya kandungan
unsur hara yang terbawa oleh sedimen dan besarnya erosi yang terjadi. Di
tempat lain, erosi menyebabkan hilangnya lapisan atas tanah yang subur serta
berkurangnya kemampuan tanah untuk menyerap dan menahan air. Tanah yang
terangkut tersebut diendapkan di tempat lain yaitu, di dalam sungai, waduk,
danau, saluran irigasi dan di atas tanah pertanian.
Kalian ingin tahu apa yang menyebabkan terjadinya erosi tanah itu?
Sebab–sebab erosi tanah karena beberapa hal berikut :
1. Tanah gundul atau tidak ada tanamannya;
2. Tanah miring tidak dibuat teras–teras dan guludan sebagai penyangga air dan
tanah yang lurus;
3. Tanah tidak dibuat tanggul pasangan sebagai penahan erosi;
4. Pada tanah di kawasan hutan rusak karena pohon–pohon ditebang secara liar
sehingga hutan menjadi gundul;
5. Pada permukaan tanah yang berlumpur digunakan untuk pengembalaan liar
sehingga tanah atas semakin rusak
Kalau ada penyebab erosi tanah, apakah ada cara untuk penanggulangan
erosi tanah ? Sebagai usaha untuk mengurangi erosi tanah dapat dilakukan
upaya–upaya konservasi. Tujuan konservasi tanah adalah untuk menjaga agar
tanah tidak tererosi. Usaha–usaha konservasi tanah ditujukan untuk menjegah
kerusakan, memperbaiki dan meningkatkan produktifitas tanah agar dapat
dipergunakan secara lestari.
Tanah yang subur sangat diperlukan untuk pertanian. Pertanian dapat
memproduksi hasil bumi yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Konservasi
tanah dapat dilakukan dengan 3 metode yaitu :

73
1. Metode Vegetatif
Adalah penggunaan tanaman atau tumbuhan dan sisa–sisanya untuk
mengurangi jumlah dan daya rusak hujan yang jatuh, mengurangi jumlah dan
Gambar : countour strip cropping
a. Reboisasi adalah menanami kembali hutan yang gundul
b. Countour strip cropping adalah bercocok tanam dengan beberapa jenis
tanaman semusim dalam strip – strip yang berselang – seling menurut
garis kontur
c. Croups rotation adalah usaha penanaman jenis tanaman secara
bergantian dalam suatu lahan
2. Metode Mekanik
Adalah semua perlakuan fisik mekanik yang diberikan terhadap tanah
dan pembuatan bangunan untuk mengurangi aliran permukaan dan erosi, serta
meningkatkan kemampuan penggunaan tanah.

74
Gambar : Terassering
Berikut bentuk–bentuk metode mekanik.
a. Countour plowing adalah membajak searah garis kontur, sehingga
terjadilah alur–alur horisontal.
b. Guliudan adalah tumpukan tanah yang dibuat memanjang searah
garis kontur atau memotong lereng untuk menahan erosi
c. Terassering adalah menanam tanaman dengan sistem berteras–teras
di daerah lereng.
d. Perbaikan drainase dan irigasi.
3. Metode Kimia
Adalah dengan menggunakan preparat kimia sintetis atau alami. Preparat ini disebut Soil Conditioner atau pemantap struktur tanah. Sesuai dengan namanya Soil Conditioner ini digunakan untuk membentuk struktur tanah yang stabil. Senyawa yang terbentuk akan menyebabkan tanah menjadi stabil .

75
G. Pencemaran Udara
Pencemaran lingkungan yang paling mempengaruhi keadaan iklim dunia
adalah pencemaran udara. Pencemaran udara ini menimbulkan berbagai
dampak negatif bagi kehidupan di muka bumi. Semakin menipisnya lapisan ozon
adalah salah satu dampak yang harus diwaspadai karena ini berarti menyangkut
lestarinya keanekaragaman hayati, kelangsungan makhluk hidup di bumi, dan
keberadaan bumi itu sendiri.
Pencemaran udara adalah peristiwa masuknya, atau tercampurnya,
polutan (unsur-unsur berbahaya) ke dalam lapisan udara (atmosfer) yang dapat
mengakibatkan menurunnya kualitas udara (lingkungan).
Pencemaran dapat terjadi dimana-mana. Bila pencemaran tersebut
terjadi di dalam rumah, di ruang-ruang sekolah ataupun di ruang-ruang
perkantoran maka disebut sebagai pencemaran dalam ruang (indoor pollution),
sedangkan bila pencemarannya terjadi di lingkungan rumah, perkotaan, bahkan
regional maka disebut sebagai pencemaran di luar ruang (outdoor pollution).
Umumnya, polutan yang mencemari udara berupa gas dan asap. Gas dan
asap tersebut berasal dari hasil proses pembakaran bahan bakar yang tidak
sempurna, yang dihasilkan oleh mesin-mesin pabrik, pembangkit listrik dan
kendaraan bermotor. Selain itu, gas dan asap tersebut merupakan hasil oksidasi
dari berbagai unsur penyusun bahan bakar, yaitu: CO2 (karbondioksida), CO
(karbonmonoksida), SOx (belerang oksida) dan NOx (nitrogen oksida).
1. Faktor Penyebab Pencemaran Udara
Pencemaran udara disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
a. Faktor alam (internal), yang bersumber dari aktivitas alam. Contoh:
1) abu yang dikeluarkan akibat letusan gunung berapi
2) gas-gas vulkanik
3) debu yang beterbangan di udara akibat tiupan angin
4) bau yang tidak enak akibat proses pembusukan sampah organik

76
b. Faktor manusia (eksternal), yang bersumber dari hasil aktivitas manusia
1) hasil pembakaran bahan-bahan fosil dari kendaraan bermotor
2) bahan-bahan buangan dari kegiatan pabrik industri yang memakai zat kimia
organik dan anorganik
3) pemakaian zat-zat kimia yang disemprotkan ke udara
4) pembakaran sampah rumah tangga
5) pembakaran hutan
2. Sumber Pencemar Udara
Telah disadari bersama, kualitas udara saat ini telah menjadi persoalan
global, karena udara telah tercemar akibat aktivitas manusia dan proses alam.
Masuknya zat pencemar ke dalam udara dapat secara alamiah, misalnya asap
kebakaran hutan, akibat gunung berapi, debu meteorit dan pancaran garam dari
laut ; juga sebagian besar disebabkan oleh kegiatan manusia, misalnya akibat
aktivitas transportasi, industri, pembuangan sampah, baik akibat proses
dekomposisi ataupun pembakaran serta kegiatan rumah tangga
Terdapat 2 jenis pencemar yaitu sebagai berikut :
a. Zat pencemar primer, yaitu zat kimia yang langsung mengkontaminasi
udara dalam konsentrasi yang membahayakan. Zat tersebut bersal dari
komponen udara alamiah seperti karbon dioksida, yang meningkat di atas

77
konsentrasi normal, atau sesuatu yang tidak biasanya, ditemukan dalam
udara, misalnya timbal.
b. Zat pencemar sekunder, yaitu zat kimia berbahaya yang terbentuk di
atmosfer melalui reaksi kimia antar komponen-komponen udara.
Sumber bahan pencemar primer dapat dibagi lagi menjadi dua golongan
besar :
a. Sumber alamiah
Beberapa kegiatan alam yang bisa menyebabkan pencemaran udara
adalah kegiatan gunung berapi, kebakaran hutan, kegiatan
mikroorganisme, dan lain-lain. Bahan pencemar yang dihasilkan
umumnya adalah asap, gas-gas, dan debu.
b. Sumber buatan manusia
Kegiatan manusia yang menghasilkan bahan-bahan pencemar bermacam-
macam antara lain adalah kegiatan-kegiatan berikut :
1) Pembakaran, seperti pembakaran sampah, pembakaran pada kegiatan
rumah tangga, industri, kendaraan bermotor, dan lain-lain. Bahan-
bahan pencemar yang dihasilkan antara lain asap, debu, grit (pasir
halus), dan gas (CO dan NO).
2) Proses peleburan, seperti proses peleburan baja, pembuatan
soda,semen, keramik, aspal. Sedangkan bahan pencemar yang
dihasilkannya antara lain adalah debu, uap dan gas-gas.
3) Pertambangan dan penggalian, seperti tambang mineral and logam.
Bahan pencemar yang dihasilkan terutama adalah debu.
4) Proses pengolahan dan pemanasan seperti pada proses pengolahan
makanan, daging, ikan, dan penyamakan. Bahan pencemar yang
dihasilkan terutama asap, debu, dan bau.

78
5) Pembuangan limbah, baik limbah industri maupun limbah rumah
tangga. Pencemarannya terutama adalah dari instalasi pengolahan air
buangannya. Sedangkan bahan pencemarnya yang teruatam adalah gas
H2S yang menimbulkan bau busuk.
6) Proses kimia, seperti pada proses fertilisasi, proses pemurnian minyak
bumi, proses pengolahan mineral. Pembuatan keris, dan lain-lain.
Bahan-bahan pencemar yang dihasilkan antara lain adalah debu, uap
dan gas-gas.
7) Proses pembangunan seperti pembangunan gedung-gedung, jalan dan
kegiatan yang semacamnya. Bahan pencemarnya yang terutama adalah
asap dan debu.
8) Proses percobaan atom atau nuklir. Bahan pencemarnya yang terutama
adalah gas-gas dan debu radioaktif.
Ada beberapa polutan yang dapat menyebabkan pencemaran udara,
antara lain: Karbon monoksida, Nitrogen dioksida, Sulfur dioksida, Partikulat,
Hidrokarbon, CFC, Timbal, dan Karbondioksida.
a. Karbon monoksida (CO)
Gas yang tidak berwarna, tidak berbau dan bersifat racun. Dihasilkan dari
pembakaran tidak sempurna bahan bakar fosil, misalnya gas buangan
kendaraan bermotor.
b. Nitrogen dioksida (NO2)
Gas yang paling beracun. Dihasilkan dari pembakaran batu bara di pabrik,
pembangkit energi listrik dan knalpot kendaraan bermotor.
c. Sulfur dioksida (SO2)
Gas yang berbau tajam, tidak berwarna dan tidak bersifat korosi.
Dihasilkan dari pembakaran bahan bakar yang mengandung sulfur

79
terutama batubara. Batubara ini biasanya digunakan sebagai bahan bakar
pabrik dan pembangkit tenaga listrik.
d. Partikulat (asap atau jelaga)
Polutan udara yang paling jelas terlihat dan paling berbahaya. Dihasilkan
dari cerobong pabrik berupa asap hitam tebal.
e. Hidrokarbon (HC)
Uap bensin yang tidak terbakar. Dihasilkan dari pembakaran bahan bakar
yang tidak sempurna.
f. Chlorofluorocarbon (CFC)
Gas yang dapat menyebabkan menipisnya lapisan ozon yang ada di
atmosfer bumi. Dihasilkan dari berbagai alat rumah tangga seperti kulkas,
AC, alat pemadam kebakaran, pelarut, pestisida, alat penyemprot (aerosol)
pada parfum dan hair spray.
g. Timbal (Pb)
Logam berat yang digunakan manusia untuk meningkatkan pembakaran
pada kendaraan bermotor. Hasil pembakaran tersebut menghasilkan
timbal oksida yang berbentuk debu atau partikulat yang dapat terhirup
oleh manusia.

80
h. Karbon dioksida (CO2)
Gas yang dihasilkan dari pembakaran sempurna bahan bakar kendaraan
bermotor dan pabrik serta gas hasil kebakaran hutan.
Menurut data dari Departemen Kehutanan, luas kebakaran hutan di
seluruh Indonesia tahun 2002 mencapai 38.389,23 hektar dengan kerugian
Rp.122.967.050. Secara rinci luas kebakaran setiap provinsi tahun 2002 dapat
dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Kebakaran hutan diseluruh Indonesia

81
3. Dampak Pencemaran Udara
Pencemaran udara dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan
alam, antara lain: hujan asam, penipisan lapisan ozon dan pemanasan global.
a. Hujan asam
Istilah hujan asam pertama kali diperkenalkan oleh Angus Smith
ketika ia menulis tentang polusi industri di Inggris. Hujan asam adalah
hujan yang memiliki kandungan pH (derajat keasaman) kurang dari 5,6.
Proses terbentuknya hujan asam adalah SO2 dan NOx (NO2 dan
NO3) yang dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar fosil
(kendaraan bermotor) dan pembakaran batubara (pabrik dan
pembangkit energi listrik) akan menguap ke udara. Sebagian lainnya
bercampur dengan O2 yang dihirup oleh makhluk hidup dan sisanya akan
langsung mengendap di tanah sehingga mencemari air dan mineral tanah.
SO2 dan NOx (NO2 dan NO3) yang menguap ke udara akan bercampur
dengan embun. Dengan bantuan cahaya matahari, senyawa tersebut akan
diubah menjadi tetesan-tetesan asam yang kemudian turun ke bumi
sebagai hujan asam. Namun, bila H2SO2 dan HNO2 dalam bentuk butiran-
butiran padat dan halus turun ke permukaan bumi akibat adanya gaya
gravitasi bumi, maka peristiwa ini disebut dengan deposisi asam.
b. Penipisan lapisan ozon
Ozon (O3) adalah senyawa kimia yang memiliki 3 ikatan yang tidak
stabil. Di atmosfer, ozon terbentuk secara alami dan terletak di lapisan
stratosfer pada ketinggian 15-60 km di atas permukaan bumi. Fungsi dari
lapisan ini adalah untuk melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet
yang dipancarkan sinar matahari dan berbahaya bagi kehidupan.
Namun, zat kimia buatan manusia yang disebut sebagai ODS
(Ozone Depleting Substances) atau BPO (Bahan Perusak Ozon) ternyata
mampu merusak lapisan ozon sehingga akhirnya lapisan ozon menipis.

82
Hal ini dapat terjadi karena zat kimia buatan tersebut dapat
membebaskan atom klorida (Cl) yang akan mempercepat lepasnya ikatan
O3 menjadi O2. Lapisan ozon yang berkurang disebut sebagai lubang ozon
(ozone hole).
Gambar: Lubang Ozon
Diperkirakan telah timbul adanya lubang ozon di Benua Artik dan
Antartika. Oleh karena itulah, PBB menetapkan tanggal 16 September
sebagai hari ozon dunia dengan tujuan agar lapisan ozon terjaga dan
tidak mengalami kerusakan yang parah.
c. Pemanasan global (global warming)
Global warming atau pemanasan global adalah proses
peningkatan suhu bumi yang diakibatkan oleh efek rumah kaca. Apakah
efek rumah kaca tersebut? Efek rumah kaca adalah efek yang dihasilkan
gas-gas rumah kaca yang menahan sinar matahari agar tetap di dalam
bumi dan tidak mengalami radiasi ke luar angkasa. Efek rumah kaca
(green house effect) ini sangat berguna bagi kehidupan di bumi karena
jika tidak ada efek ini, suhu bumi akan sangat dingin. Efek rumah kaca ini
mempengaruhi terjadinya kenaikan suhu udara di bumi (pemanasan
global). Pemanasan global adalah kenaikan suhu rata-rata di seluruh
dunia dan menimbulkan dampak berupa berubahnya pola iklim.
Peristiwa efek rumah kaca adalah permukaan bumi akan
menyerap sebagian radiasi matahari yang masuk ke bumi dan
memantulkan sisanya. Namun, karena meningkatnya CO2 di lapisan

83
atmosfer maka pantulan radiasi matahari dari bumi ke atmosfer tersebut
terhalang dan akan kembali dipantulkan ke bumi. Akibatnya, suhu di
seluruh permukaan bumi menjadi semakin panas (pemanasan global).
Peristiwa ini sama dengan yang terjadi di rumah kaca. Rumah kaca
membuat suhu di dalam ruangan rumah kaca menjadi lebih panas bila
dibandingkan di luar ruangan. Hal ini dapat terjadi karena radiasi
matahari yang masuk ke dalam rumah kaca tidak dapat keluar.
d. Dampak pencemaran udara bagi manusia
1) Meningkatnya Karbon monoksida (CO) mampu mengikat Hb
(hemoglobin) sehingga pasokan O2 ke jaringan tubuh terhambat. Hal
tersebut menimbulkan gangguan kesehatan berupa; rasa sakit pada
dada, nafas pendek, sakit kepala, mual, menurunnya pendengaran dan
penglihatan menjadi kabur. Selain itu, fungsi dan koordinasi motorik
menjadi lemah. Bila keracunan berat (70 : 80 % Hb dalam darah telah
mengikat CO), dapat menyebabkan pingsan dan diikuti dengan
kematian.
2) Meningkatnya Nitrogen dioksida (SO2) dapat menyebabkan timbulnya
serangan asma.
3) Meningkatnya Hidrokarbon (HC) dapat menyebabkan kerusakan
otak, otot dan jantung.
4) Meningkatnya Chlorofluorocarbon (CFC) dapat menyebabkan
melanoma (kanker kulit) khususnya bagi orang-orang berkulit terang,
katarak dan melemahnya sistem daya tahan tubuh
5) Meningkatnya Timbal (Pb) dapat menyebabkan gangguan pada tahap
awal pertumbuhan fisik dan mental serta mempengaruhi kecerdasan otak.
6) Meningkatnya Ozon (O3) dapat menyebabkan iritasi pada hidung,
tenggorokan terasa terbakar dan memperkecil paru-paru.

84
H. Upaya Penanggulangan Pencemaran Udara
Upaya penanggulangan dilakukan dengan tindakan pencegahan
(preventif) yang dilakukan sebelum terjadinya pencemaran dan tindakan kuratif
yang dilakukan sesudah terjadinya pencemaran.
1. Usaha Preventif (sebelum pencemaran)
a. Mengembangkan energi alternatif dan teknologi yang ramah lingkungan.
b. Mensosialisasikan pelajaran lingkungan hidup (PLH) di sekolah dan
masyarakat.
c. Mewajibkan dilakukannya AMDAL (Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan) bagi industri atau usaha yang menghasilkan limbah.
d. Tidak membakar sampah di pekarangan rumah.
e. Tidak menggunakan kulkas yang memakai CFC (freon) dan membatasi
penggunaan AC dalam kehidupan sehari-hari.
f. Tidak merokok di dalam ruangan.
g. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan penghijauan.
h. Ikut memelihara dan tidak mengganggu taman kota dan pohon pelindung.
Seseorang yang batuk-batuk
karena daya tahan tubuhnya
menurun
Orang yang sedang demam
(influenza/pilek)

85
i. Tidak melakukan penebangan hutan, pohon dan tumbuhan liar secara
sembarangan.
j. Mengurangi atau menghentikan penggunaan zat aerosol dalam
penyemprotan ruang.
k. Menghentikan penggunaan busa plastik yang mengandung CFC.
l. Mendaur ulang freon dari mobil yang ber-AC.
m. Mengurangi atau menghentikan semua penggunaan CFC dan CCl4.
n. Keharusan membuat cerobong asap bagi industri/pabrik.
Orang sedang membakan sampah Orang sedang merokok
Orang sedang menebang pohon

86
2. Usaha Kuratif (sesudah pencemaran)
b. Menggalang dana untuk mengobati dan merawat korban pencemaran
lingkungan.
c. Kerja bakti rutin di tingkat RT/RW atau instansi-instansi untuk
membersihkan lingkungan dari polutan.
d. Melokalisasi tempat pembuangan sampah akhir (TPA) sebagai
tempat/pabrik daur ulang.
e. Menggunakan penyaring pada cerobong-cerobong di kilang minyak atau
pabrik yang menghasilkan asap atau jelaga penyebab pencemaran udara.
f. Mengidentifikasi dan menganalisa serta menemukan alat atau teknologi
tepat guna yang berwawasan lingkungan setelah adanya
musibah/kejadian akibat pencemaran udara, misalnya menemukan bahan
bakar dengan kandungan timbal yang rendah (BBG).
Gambar. Masyarakat yang sedang kerja bakti menanam pohon

87
BAB IX BENTUK-BENTUK KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN
FAKTOR PENYEBABNYA
Lingkungan hidup mempunyai keterbatasan, baik dalam hal kualitas
maupun kuantitasnya. Dengan kata lain, lingkungan hidup dapat mengalami
penurunan kualitas dan penurunan kuantitas. Penurunan kualitas dan kuantitas
lingkungan ini menyebabkan kondisi lingkungan kurang atau tidak dapat
berfungsi lagi untuk mendukung kehidupan makhluk hidup yang ada di
dalamnya. Kerusakan lingkungan hidup dapat disebabkan oleh beberapa faktor.
Berdasarkan penyebabnya, kerusakan lingkungan dapat dikarenakan
proses alam dan karena aktivitas manusia.
1. Kerusakan Lingkungan Akibat Proses Alam
Kerusakan lingkungan hidup oleh alam terjadi karena adanya gejala atau
peristiwa alam yang terjadi secara hebat sehingga mempengaruhi keseimbangan
lingkungan hidup. Peristiwa-peristiwa alam yang dapat mempengaruhi
kerusakan lingkungan, antara lain meliputi hal-hal berikut ini.
a. Letusan gunung api
Letusan gunung api dapat menyemburkan lava, lahar, material-
material padat berbagai bentuk dan ukuran, uap panas, serta debu-debu
vulkanis. Selain itu, letusan gunung api selalu disertai dengan adanya
gempa bumi lokal yang disebut dengan gempa vulkanik.
Aliran lava dan uap panas dapat mematikan semua bentuk
kehidupan yang dilaluinya, sedangkan aliran lahar dingin dapat
menghanyutkan lapisan permukaan tanah dan menimbulkan longsor lahan.
Uap belerang yang keluar dari pori-pori tanah dapat mencemari tanah dan
air karena dapat meningkatkan kadar asam air dan tanah. Debu-debu
vulkanis sangat berbahaya bila terhirup oleh makhluk hidup (khususnya
manusia dan hewan), hal ini dikarenakan debu-debu vulkanis mengandung

88
kadar silika (Si) yang sangat tinggi, sedangkan debu-debu vulkanis yang
menempel di dedaunan tidak dapat hilang dengan sendirinya. Hal ini
menyebabkan tumbuhan tidak bisa melakukan fotosintesis sehingga
lambat laun akan mati. Dampak letusan gunung memerlukan waktu
bertahun-tahun untuk dapat kembali normal. Lama tidaknya waktu untuk
kembali ke kondisi normal tergantung pada kekuatan ledakan dan tingkat
kerusakan yang ditimbulkan. Akan tetapi, setelah kembali ke kondisi
normal, maka daerah tersebut akan menjadi daerah yang subur karena
mengalami proses peremajaan tanah.
b. Gempa bumi
Gempa bumi adalah getaran yang ditimbulkan karena adanya
gerakan endogen. Semakin besar kekuatan gempa, maka akan
menimbulkan kerusakan yang semakin parah di muka bumi. Gempa bumi
menyebabkan bangunan-bangunan retak atau hancur, struktur batuan
rusak, aliran-aliran sungai bawah tanah terputus, jaringan pipa dan saluran
bawah tanah rusak, dan sebagainya. Jika kekuatan gempa bumi melanda
lautan, maka akan menimbulkan tsunami, yaitu arus gelombang pasang air
laut yang menghempas daratan dengan kecepatan yang sangat tinggi.
Masih ingatkah kalian dengan peristiwa tsunami di Nanggroe Aceh
Darussalam di penghujung tahun 2004 yang lalu? Contoh peristiwa gempa
bumi yang pernah terjadi di Indonesia antara lain gempa bumi yang terjadi
pada tanggal 26 Desember 2004 di Nanggroe Aceh Darussalam dengan
kekuatan 9,0 skala richter. Peristiwa tersebut merupakan gempa paling
dasyat yang menelan korban diperkirakan lebih dari 100.000 jiwa. Gempa
bumi juga pernah melanda Yogyakarta dan Jawa Tengah pada bulan Mei
2006 dengan kekuatan 5,9 skala richter. Dalam al-Qur’an surat al-Ankabut
(29): 37 dijelaskan:
ا ا ا ل ا ا يا ذ وا ا الذ

89
Artinya: Maka mereka mendustakan Syu'aib, lalu mereka ditimpa gempa yang dahsyat, dan jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka.
Akibat terjadinya gempa, permukaan tanah dapat menjadi retak
atau turun, sehingga terjadilah longsor. Jika tanah longsor ini terjadi pada
bagian tebing, tanah longsoran akan menutup bagian lembah. Dengan
demikian, terjadilah sautu perubahan bentuk lembah menjadi permukaan
yang rata dan dapat digunakan untuk tanah pertanian.
Cara paling efketif untuk mengurangi kerusakan yang disebabkan
oleh gempa ialah dengan program reduksi bahaya (hazard reduction).
Pendekatan ini mengakui ketidakmampuannya untuk menghindari
terjadinya gempa bumi dan hanya berusaha mengurangi dampaknya di
daerah-daerah yang padat penduduknya.
Dua kunci persyaratan, yakni mendeteksi daerah-daerah dengan
resiko gempa yang tinggi dan kemampuan merencanakan bangunan yang
akan tahan terhadap goncangan, ditetapkan dengan menggabungkan
penelitian geologi; menghimpun catatan-catatan dari goncangan-
goncangan yang telah terjadi dan tumbuhnya ilmu pengetahuan seismologi.
Pengamatan fenomena-fenomena yang mendahului terjadinya
gempa menimbulkan ilmu pengetahuan baru; ramalan gempa atau
earthquake prediction. Beberapa gempa bumi dapat diramalkan oleh teori
baru yang meliputi seismic gaps.
Pada beberapa gempa dengan magnitude 4,5 sampai 6,5 yang telah
terjadi di Indonesia dalam jangka waktu 15 tahun terakhir ini, telah
menimbulkan bencana yang merugikan masyarakat di wilayah yang
terkena gempa. Kerugian umum terjadi adalah rusak dan robohnya
bangunan, khususnya rumah tinggal dan bangunan.

90
Terhadap fenomena gempa bumi ini, orang dengan akal pikirannya
semata-mata tidak mudah memberikan interpretasi mengenai hikmah
yang terkandung di dalamnya. Oleh sebab itu terdapat berbgai macam
interpretasi yang berusaha menerangkan hikmah adanya musibah gempa.
Adapun keterangan dari al-Qur’an menjelaskan bahwa semua macam
fenomena alam menunjukkan adanya perencanaan yang rumit dan maksud
yang jelas. Oleh sebab itu kita disuruh menjadi ulul albab, orang yang mau
memikirkan. Yang akhirnya berkesimpulan bahwa, segala ciptaan Allah
dengan fenomena-fenomenanya itu pasti tidak sia-sia dan merupakan bukti
keagungan-Nya, sesuai firman-Nya dalam Qs. Ali-Imran (3): 191:
اذ يا ل يااللاق ا قع ا علىا ن ا ذل يا ا لقا اسذ تا لألضا
ال ذن ا ا ل تا ا ا اس ن ا ن اع اا انذ لا
Artinya: (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan Ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka.
Adanya musibah gempa bumi memberikan pengertian dan
gambaran kepada umat manusia akan dahsyatnya mekanisme hari qiyamat
sebagaiamana dilukiskan dalam QS. Al-Zalzalah (99): 1-2.
{2} أ ل تا لألضاأا ا اا{1}إ ازازاتا لألضازاز ا ا
Artinya: (1) Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan (yang dahsyat),(2). Dan bumi Telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung)nya.
Gempa bumi yang hebat yang terjadi kelak pada hari qiyamat dapat
dibayangkan bagaimana dahsyatnya, mengingat gempa bumi yang kini
terjadi secara lokal sudah demikian besar dan membawa kematian banyak
orang dan robohnya banyak gedung. Demikian pula pada hari qiyamat

91
segala isi bumi dikeluarkan, yang berupa emas, perak, besi, tembaga, dan
juga tulang belulang menggambarkan betapa dahsyatnya waktu itu. Kini
perbendaharaan bumi berupa bijih besi, emas, perak berhasilkan
dikeluarkan oleh pakar-pakar teknik. Pengeboran bensin dan gas dari
dalam tanah mengeluarkan semprotan gas dan cairan yang dahsyat disertai
energi panas yang sangat tinggi seperti di Porong , Sidoarjo, Jawa Timur.
Maka dapat dibayangkan nanti pada hari qiyamat, bila segala isi
perbendaharaan bumi dikeuarkan disertai gempa yang tidak bersifat lokal
tetapi menyeluruh di semua permukaan bumi.
c. Banjir
Banjir adalah salah satu peristiwa alam yang sering terjadi. Banjir
dapat melanda daerah perkotaan atau pedesaan. Banjir sering
mengakibatkan kerugian, bahkan dapat menghancurkan rumah-rumah
penduduk. Pada akhir tahun 2002, hujan deras yang terjadi di Indonesia
mengakibatkan banjir di beberapa tempat yang menimbulkan kerugian
besar bagi penduduk yang terkena banjir. Misalnya, hancurnya tiga
perkampungan di daerah Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut sebagai
akibat banjir dan tanah longsor dari gunung Mandalawangi yang terjadi
pada tanggal 29 Januari 2003. Tanah longsor ini menimpa rumah-rumah
penduduk. Hampir setiap musim hujan tahun di beberapa tempat di Jakarta
mengalami banjir yang mengakibatkan kerugian besar bagi penduduk.
Terjadinya banjir sering berkaitan dengan ulah manusia dalam
mengelola lingkungannya. Menurut keterangan, banjir lumpur yang
menimpa Wana Wisata Pacet, Mojokerto, pada bulan Desember 2002
diakibatkan oleh gundulnya lereng Gunung Liran. Keadaan ini akibat dari
kegiatan manusia yang menebangi pepohonan di lereng gunung hingga
gundul. Jika terjadi hujan deras, air hujan akan segera mengalir ke bawah
mengikis tanah, dan terjadilah banjir lumpur yang menimpa tempat-

92
tempat yang ada di bawahnya. Banjir lumpur PT. Lapindo di Porong
Sidoarjo menambah deretan fenemona alam akibat salah urus ataupun
terlalu banyak mengekploitasi alam, tanpa memperhatikan habitat dan
keberlangsungannya.
Banjir di perkotaan sering juga disebabkan oleh tersumbatnya
saluran-saluran air oleh sampah-sampah yang dibuang penduduk ke
saluran air tersebut. Kadang-kadang banjir dapat memberi keuntungan
kepada manusia jika banjir itu merupakan luapan air sungai. Tetapi selama
ini terjadi, banjir lebih banyak menelan korban seperti yang terjadi di Aceh
dan Mandailing Natal, Sumatera Utara akhir tahun 2006 kemarin.
Memang manusia hari ini seakan-akan telah menyingkirkan Tuhan
dari hidupnya. Mereka seakan-akan tidak lagi mengakui hak-hak Tuhan
atas mereka bahkan merampasnya. Hak-hak Tuhan adalah hak
kemanusiaan, karena Tuhan melalui ajaran-Nya memang hadir untuk
manusia, kemanusiaan dan alam. Dia menganugerahkan alam semesta
untuk kesejahteraan semesta. Allah menyatakan dalam QS. Al-Mukminun
(23): 18-21.
ءا ءا لا س نذ وا ا لألضا إنذ اعلىا اا هاا ل يا نش ن اا ا هااا{18} أنزان ا يا اسذ
يانذ لا أعن اااذ ا ا ها الةا ن ا ل يا ن ءاا{19} نذ تا ش لةا لجا ياا لاس
اا ا ا لأنع ااع لةانس ا ذ ا ا ا ن ا ا ا ا ن عاا{20}ا ن تا ا يا غاال ليا إيذ
{21}ا الةا ن ا ل يا
Artinya:(18) Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran; lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan Sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya; (19) Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur; di dalam kebun-kebun itu kamu peroleh buah-buahan yang banyak dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan ; (20) Dan pohon kayu keluar dari Thursina (pohon zaitun), yang menghasilkan minyak, dan pemakan makanan bagi orang-orang yang makan ; (21) Dan Sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu, kami memberi minum

93
kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan.
Tuhan melalui firman di atas mengingatkan agar manusia kembali
kepada Tuhan. Jika semua orang beragama mengakui dan meyakini bahwa
hanya Tuhan satu-satunya yang harus disembah, dicintai dan diagungkan
serta dipuja, maka pernyataan dan keyakinan ini akan membawa
konsekuensi yang bersifat sosial, kemanusiaan dan alam. Dengan kata lain
keyakinan ini seharusnya merefleksikan cita-cita kemanusiaan universal,
kemanusiaan sejagat dan kelestarian alam. Cita-cita itu adalah mencintai
manusia, menghormati hak-hak mereka, melindungi alam dan
melestarikannya, serta memanfaatkannya demi kesejahteraan bersama.
Akhirnya untuk menghindari terjadinya banjir, perlu dilakukan
tindakan sebagai berikut:
1) Tidak menebang pohon atau hutan secara liar, pembakaran hutan atau
praktik illegal loging.
2) Tidak membuang sampah di sembarang tempat, terutama di selokan-
selokan ataupun di sungai-sungai.
3) Perlu dilakukan reboisasi terhadap hutan yang gundul.
4) Dalam jangka panjang perlu pemberdayaan masyarakat melalui
pendidikan yang berkesadaran lingkungan.
d. Potensi tanah longsor
Seperti yang sudah dijelaskan pada bab ini, tanah longsor
merupakan akibat dari gempa bumi. Lebih jauh daripada itu, tanah longsor
berpotensi terjadi pada jenis permukaan bumi pada dataran tinggi yang
telah terjamah oleh ulah tangan manusia yang menggunduli hutan tanpa
adanya reboisasi. Seperti halnya yang sedang terjadi pada tahun 2009 ini.
Di Gunung Simba ±5 km sebelah selatan desa Pelangan, dusun

94
Mencanggah, kecamatan Sekotong Tengah, Lombok Barat, Nusa Tenggara
Barat. Telah terjadi pembabatan hutan sekaligus penggalian material tanah
yang mengandung unsur emas yang cukup tinggi. Pohon-pohon pada
permukaan Gunung Simba ditebang dan dibuat lahan galian sedalam 25
meter dan telah mencapai hampir 1 km ke samping. Hal itu memungkinkan
terjadinya tanah longsor dan akan merembet menutup daerah dataran
rendah.
NTB yang telah menjadi pusat sorotan dunia karena potensi
tanahnya yang mengandung emas (terutama di kabupaten Sumbawa dan
Kabupaten Lombok Barat), memungkinkan terjadinya krisis ekologi besar-
besaran. Hal tersebut teridentifikasi bahwa pada titik-titik penambangan
emas di daerah NTB, puluhan orang tertimbun longsor dan tidak diketahui
asal usul tempat tinggalnya. Sehingga mereka meninggal tanpa diketahui
oleh sanak keluarganya. Hal tersebut menunjukkan betapa
memperihatikannya manusia pada tempat tersebut.
Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW “dari Az-Zuhri yang mendapat cerita dari Thalhah bin Abdullah; sesungguhnya Abdurrahman bi Amer bin Sahel bercerita kepadanya bahwa Sa’id bin Zaid ra berkata ; “ Barang siapa yang berlaku zalim terhadap suatu tanah, maka tujuh lapis bumi akan ditimpakan pada kepalanya”. (HR.Bukhari)
e. Badai/Angin Topan
Angin topan terjadi karena perbedaan tekanan udara yang sangat
mencolok di suatu daerah sehingga menyebabkan angin bertiup lebih
kencang. Di beberapa belahan dunia, bahkan sering terjadi pusaran angin.
Bencana alam ini pada umumnya merusakkan berbagai tumbuhan,
memorakporandakan berbagai bangunan, sarana infrastruktur dan dapat
membahayakan penerbangan. Badai atau angin topan sering melanda
beberapa daerah tropis di dunia termasuk Indonesia. Beberapa daerah di

95
Indonesia pernah dilanda gejala alam ini. Salah satu contoh adalah angin
topan yang melanda beberapa daerah di Yogyakarta dan Jawa Tengah.
f. Kemarau Panjang
Bencana alam ini merupakan kebalikan dari bencana banjir.
Bencana ini terjadi karena adanya penyimpangan iklim yang terjadi di
suatu daerah sehingga musim kemarau terjadi lebih lama dari biasanya.
Bencana ini menimbulkan berbagai kerugian, seperti mengeringnya sungai
dan sumber-sumber air, munculnya titik-titik api penyebab kebakaran
hutan, dan menggagalkan berbagai upaya pertanian yang diusahakan
penduduk.
g. Tsunami sebagai Fenomena Alam
Indonesia yang memiliki pantai terpanjang di dunia dan terletak di
daerah berkerak bumi yang labil, mempunyai potensi besar terhadap
kemungkinan terjadinya tsunami. Potensi tersebut menjadi lebih besar lagi
karena sebagian besar pusat gempa bumi tektonik, yang menjadi penyebab
utama tsunami, terletak di dasar lautan dan sambung menyambung
sepanjang pantai mulai dari pantai barat Sumatera, pantai selatan Jawa,
pantai di pulau-pulau Nusa Tenggara, Maluku sampai Sulawesi Selatan.
Sejak tahun 1900 sudah tercatat stidaknya sepuluh kali tsunami di
pantai-pantai Indonesia, atau rata-rata satu kejadian setiap sembilan tahun.
Tenggang waktu terjadinya di Aceh (2004) kira-kira sepuluh tahun dengan
tsunami yang terjadi di Bayuwangi (1994). Seperti diketahui Minggu
tanggal 26 Desember 2004, sekitar pukul 07.00 WIB pada lokasi 3,307 LU,
95,947 BT atau dilepas pantai sebelah Barat Sumatera bagian utara,
permukaan air laut Samudra Hindia berombak seperti biasa. Beberapa
kapal bertolak dari dermaga kecil di pesisir Meunasah Tuha, Aceh Besar
menuju perairan Ujung Pancuh yang merupakan ladang ikan bagi nelayan.
Langit pagi itu cerah dengan sedikit awan tipis menghiasi cakrawala. Lima

96
puluh delapan menit lepasnya dari pukul tujuh saat sebuah goncangan
yang keras di kedalaman 30 km menggetarkan kapal Maberut yang
dinahkodai Usman (58). Berdasarkan pengalamannya melaut, Usman
faham betul bahwa ada gempa di laut. Kali ini luar biasa hebat, hanya saja
mungkin Usman tidak mengira apa yang bakal terjadi setelah gempa bumi
itu berlalu.
Sementara itu kota Banda Aceh yang berjarak sekitar 255 km dari
pusat gempa, tampak beberapa bangunan hancur dan porak poranda
akibat gempa yang mempunyai magnitude 9 skala Richter tersebut. Namun
hari itu adalah hari minggu, hari libur kedua setelah sehari sebelumnya
libur juga tanggal merah, libur Natal. Hari keluarga yang cerah dan sangat
nyaman bagi rakyat Aceh yang dinamis. Sejenak memang panik, namun
setelah itu pasar Aceh kembali ramai dengan aktifitas penjual dan pembeli
yang saling tawar menawar. Alun-alun kota Banda Aceh yang berada di
depan masjid Raya Baiturrahman nan megah juga kembali ramai dengan
kegiatan beberapa ibu-ibu yang melanjutkan senam pagi bersama.
Sementara anak-anak kembali bermain dipinggir pantai, apalagi air pantai
menyusut sekitar 30 meter dan banyak ikan menggelepar-gelepar seakan-
akan dengan sukarela minta untuk segera dipungut.
Namun tidak ada seorang pun yang mengira ketika 15 menit
kemudian kehangatan itu hilang berganti dengan isak tangis ketika dengan
suara dengungan yang amat keras, air laut naik kedaratan. Tingginya
bervariasi dari 3 sampai 35 meter dengan kecepatan rata-rata
7 meter/detik. Tsunami menyapu seluruh yang bisa dilewati hingga sejauh
3 km ke daratan. Ternyata gelombang tersebut tidak hanya menyapu
negeri Serambi Mekah saja, tetapi juga menghantam Thailand, Srilangka,
India, Malaysia, Maladewa, bahkan sampai semenanjung Afrika dan Kutub
Selatan. Beberapa jam setelah kejadian tersebut ada sebuah kata yang

97
paling sering disebut-sebut dilayar kaca, dan sehari kemudian kata
tersebut juga muncul dihampir seluruh media massa dunia. Kata tersebut
adalah “Tsunami”.
1) Pengertian Tsunami dan Penyebabnya.
Tsunami (diucapkan Soo-nah-mee) adalah gelombang lautan yang
sangat penjang disebabkan oleh terjadinya gangguan di bawah air
sehingga menyebabkan disposisi air secara vertikal. Istilah tsunami
diambil dari bahasa Jepang, yaitu tsu dan nami. Tsu berarti pelabuhan,
sementara nami berarti gelombang. Diambil dari bahasa Jepang karena
Jepang merupakan negara yang mempunyai sejarah paling panjang
apabila wacana tsunami didiskusikan, dan negara inilah yang paling
sering “dikunjungi” tsunami. Terminologi tsunami mulai digunakan
secara internasional pada tahun 1963 dalam suatu konferensi ilmu
pengetahuan.
Tsunami disebabkan oleh beberapa hal seperti: gempa bumi,
letusan gunung berapi, tanah longsor, ledakan bawah air, dan tumbukan
meteorit. Pada tahun 1650-1600 SM pernah terjadi tsunami yang
diakibatkan oleh letusan di Pulau Santorini, Yunani. Santorini adalah
pulau vulkanik di laut Aegean, sekitar 75 KM sebelah tenggara Yunani,
dikhabarkan bahwa letusan gunungnya memicu tsunami setinggi 100-
150 M, dan hempasannya menghancurkan pesisir utara Pulau Kreta
sejauh 70 KM, termasuk armada Minoan di sepanjang Pulau Kreta.
Sedangkan Indonesia sendiri juga mempunyai catatan memilukan
mengenai tsunami yang dipicu oleh letusan gunung, pada tanggal yang
sama dengan tanggal terjadinya tsunami di Aceh, yaitu tanggal 26
Agustus 1883, gunung Krakatau yang terletak di Selat Sunda meletus dan
menimbulkan bencana yang luar biasa. Letusan yang diperkirakan setara
dengan 200 megaton TNT sehingga sebagian pulau hancur dan lenyap

98
dari permukaan laut. Gelombang tsunami setinggi 30-40 meter
meluluhlantakkan Lampung dan Banten, bahkan mencapai wilayah
Samudra Hindia, Samudra Pasifik, Amerika Utara, Pesisir barat Amerika
Serikat, serta terusan Inggris.
Tsunami yang disebabkan oleh letusan gunung merapi memang
dahsyat, namun frekuensi terjadinya masih sangat kecil dibandingkan
dengan tsunami yang dipicu oleh gempa bumi. Menurut catatan sejarah,
80% tsunami terjadi oleh karena gempa bumi. Gerak lempeng kerak bumi
inilah yang menyebabkan gempa bahkan tsunami,1 dalam Qs. al-Qamar
(54): 11-12:
ن لا ءا ءا لن ا لألضاع ن ا ا ىا ا ءاعلىاأ لاق اق لاا{11} ن اأ اا اسذ {12} ذ
Artinya:(11) Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan (menurunkan) air yang tercurah, (12) Dan kami jadikan bumi memancarkan mata air-mata air, Maka bertemu- lah air-air itu untuk suatu urusan yang sungguh Telah ditetapkan.
Yang kemudian menjadi pertanyaannya adalah: bagaimana cara
gempa bumi dapat menyebabkan tsunami? Untuk menjawabnya kita
akan mundur kembali menuju tahun 1912. Pada tahun 1912 Alfred
Wagener, seorang ahli meteorologi dan fisika Jerman mengemukakan
konsep ‘pengapungan benua’ (Continental Crift), dalam monografi “The
Origin Of Continents and Ocean”. Hipotesa utamanya adalah adanya satu
super continen (benua yang sangat besar) yang dinamakan Pangea
(artinya semua daratan), yang dikelilingi oleh Panthalassa (artinya semua
lautan). Hipotesa selanjutnya mengatakan 200 juta tahun yang lalu super
continent ini pecah menjadi benua-benua yang lebih kecil. Benua-benua
itu kemudian bergerak ke tempatnya, seperti yang dijumpai saat ini.
Untuk mendukung hipotesanya, Wagener mengumpulkan selain

99
kesamaan garis pantai, yaitu dijumpainya kesamaan fosil, struktur dan
bebatuan.
Namun demikian banyak ilmuwan yang belum dapat
membayangkan bagaimana satu massa benua yang sangat besar dapat
terapung dan bergerak di atas bumi yang padat dan mengapa harus
terjadi. Mengenai hal ini sebenarnya Allah telah memberi petunjuk pada
kita dalam Qs. An -Naml (27): 88:
ءاإنذهاا اش ا اذ ياأ يا لذ ا اسذ اا نعااللذ ا لذ ا ل لىا ا لا س ا ةا
لا ا عل يا
Artinya: Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. (Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Baru pada awal tahun 1960, terkumpul berbagai macam data yang
memperlihatkan bahwa benua-benua tersebut benar berpindah. Sejak itu
berkembanglah teori Tektonik Lempeng (Plate Tectonics). Kunci utama
tektonik lempeng adalah adanya lempeng litosfer yang padat dan kaku
“terapung” di atas selubung bagian atas (astesnosfer) yang bersifat
plastis, dengan kata lain seperti potongan-potongan kerupuk yang berada
di atas bubur ayam. Wajar apabila semula sulit diterima akan pemikiran
adanya benua yang padat dapat bergerak di atas bumi yang padat, namun
setelah diperoleh data bahwa bagian atas selubung bersifat mendekati
lebur atau dapat dikatakan mendekati cair dan bersifat plastis, maka
wajar bila lempeng litosfer yang padat dan kaku dapat bergerak di
atasnya. Kini diyakini bagian bumi terbentuk oleh delapan lempeng besar
dan delapan lembeng kecil. Seluruh lempeng ini akhirnya bertemu di

100
sepanjang garis-garis pembatas yang berbeda. Hal ini sesuai dengan
firman Allah swt dalam Qs.An-Naba’ (78) 6-7 :
Artinya:“Bukankah Kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak”.
Ada tiga tipe garis pembatas yang dapat dibedakan lewat gerakan
lempeng, gempa, dan gejala lain yang saling berbeda. Pada tipe pertama
batas lempeng berbentuk divergen, dimana lempeng-lempeng bergerak
saling menjauh, mengakibatkan material dari selubung naik ke atas
membentuk lantai samudra baru. Tipe kedua adalah batas konvergen,
dimana lempeng-lempeng bertemu, menyebabkan salah satu lempeng
menyusup di bawah lempeng yang lain masuk ke dalam selubung
membentuk subduction zone. Tipe kedua inilah yang menyebabkan
gempa di lepas pantai sumatera bagian barat, dimana lempeng Indo-
Australia bertemu dengan lempeng Eurosia (lempeng yang menjadi
pijakan pulau Sumatera). Tipe batas terakhir adalah batas transform,
dimana lempeng saling bergesekan tanpa membentuk atau merusak
litosfer. Daya penyebab gerak lempeng belum diketahui secara pasti,
namun pendapat yang banyak diterima saat ini adalah adanya arus
konveksi dalam selubung atau material. Proses konveksi panas adalah
kaidah kedua termodinamika atau entropi. Energi yang menggerakkan
lempeng berasal dari panas bumi yang tidak hanya terpusat pada inti
bumi namun menyebar keluar sepanjang waktu. Konveksi di dalam
selubung bumi dikendalikan oleh gravitasi dan sifat bebatuan yang
mengkerut bila ia mendingin.
2) Potensi Tsunami di Indonesia dan Cara Mengantisipasinya.
Letak Indonesia yang merupakan tempat pertemuan tiga lempeng
benua (Eurosia, Indo-Australia dan Filipina) dan temasuk dalam Pacific
Seismic Belt sangatlah unik. Sejak zaman dahulu wilayah yang

101
mempunyai ribuan pulau ini telah mendapat julukan Nusantara yang
artinya kepulaun antara. Antara dua paparan benua, antara dua
samudera, antara dua jalur pelayaran. Mempunyai dua palung yang
sangat dalam dan ratusan gunung berapi yang sangat aktif. Maka julukan
sebagai “ring of fire and eartquake” pantas disandang, sebagai
konsekuensinya maka dua ratus juta penduduk di nusantara ini harus
akrab dengan bencana dan berkahnya tanah nusantara mempunyai relief
lukisan alam yang sangat indah dengan tanah yang banyak mengandung
mineral dan terkenal subur.
Apa yang terjadi di Aceh dan Nias merupakan gabungan antara
gempa dan tsunami dalam skala yang besar, terutama dalam jumlah
korban jiwa. Tsunami yang terjadi dipicu oleh gempa bumi yang
disebabkan reaksi balik dari lempeng Eurosia yang ditunjam oleh
lempeng Indo-Australia. Secara rata-rata gerakan penunjaman ini sangat
lambat, sekitar 0,5-5 cm tiap tahun dan terjadi selama 200 tahun.
Kedalaman tunjaman diperkirakan hanya dua meter namun mempunyai
panjang 500 km dan lebar 200 meter. Aksi tunjaman ini akan mencapai
klimaks dan mendapat reaksi dari lempeng yang ditunjam. Reaksi inilah
yang menyebabkan gempa. Gempa besar yang terjadi di bawah laut
dengan pusat gempa yang dangkal menyebabkan penurunan dasar laut
sehingga menyebabkan penurunan muka laut. Perubahan ini akan
mencari titik-titik keseimbangan dengan cara menjalar naik dan turun
kemana-mana. Panjang gelombang yang terjadi di laut dalam bisa
mencapai lebih dari 200 kilometer dengan kecepatan lebih dari 900
km/jam. Penjalaran itu jika mencapai paparan pantai akan meluap
dengan ketinggian sampai dengan 34 meter sejau 3 kilometer, tergantung
jenis pantai. Di Indonesia seperti yang dikemukakan oleh Dirjen Geologi
dan Sumber Daya Mineral Simon F. Sembiring (27/12/04) di Jakarta, ada

102
18 daerah rawan tsunami. Kedelapan belas daerah ini adalah NAD,
Sumut, Sumbar, Bengkulu, Lampung, Jateng dan Jatim bagian selatan,
Bali, NTT, NTB, Sulut, Sulteng, Maluku Utara dan Selatan, Biak (Yapen),
Balikpapan dan Biak.
Sebagian besar pusat gempa bumi tektonik di Indonesia terletak di
dasar lautan dan menjadi penyebab utama terjadinya tsunami. Teluk-
teluk, pelabuhan-pelabuhan, dan muara-muara sungai di sepanjang
pantai barat Sumatra, pantai selatan Jawa, pantai-pantai di Nusa
Tenggara, Maluku, sampai Sulawesi perlu diwaspadai terhadap bencana
tsunami.
Beberapa fenomena gelombang tsunami yang bisa diamati dari
pengalaman masa lalu adalah: (a) semakin besar magnitude gempa dan
semakin besar kedalaman laut dimana tectonic displacement dasar laut
terjadi, maka energi tsunami akan semakin besar, panjang gelombang
semakin besar, dan periode gelombang semakin besar, dan periode
gelombang akan semakin panjang: (b) semakin besar ke dalaman laut
maka semakin besar pula kecepatan penjalaran gelombang menuju
pantai.
Upaya yang dapat ditempuh untuk penanggulan bencana tsunami
adalah (a) penataan kembali lahan pantai, (b) pelestarian hutan
mangrove, (c) pembuatan struktur pemecah gelombang atau overtopping
seawall, (dan) membuat struktur tahan tsunami, dan (e) warning system.
2. Kerusakan Lingkungan Hidup Karena Aktivitas Manusia
Dalam memanfaatkan alam, manusia terkadang tidak memerhatikan
dampak yang akan ditimbulkan. Beberapa bentuk kerusakan lingkungan yang
dipengaruhi oleh aktivitas manusia, antara lain seperti yang sudah dijelaskan
pada BAB VIII.

103
BAB X IKLIM DAN HUJAN
A. Iklim dan Curah Hujan
Iklim Berpengaruh Bagi Kehidupan
Bumi kita senantiasa diselimuti oleh udara. Udara yang menyelimuti
bumi disebut dengan Atmosfer yang teridiri dari Gas. Atmosfer berdasarkan
temperaturnya terdiri dari beberapa lapisan, yaitu Troposfer, Stratosfer,
Mesosfer, Termosfer, dan Eksosfer. Perubahan Cuaca dan iklim terjadi pada
lapisan Troposfer yang memiliki ketinggian lapisan di khatulistiwa mencapai 19
km dan di atas kutub mencapai ketinggian 8 km, ketinggian rata-rata 11 km dari
permukaan bumi.

104
Perubahan cuaca dan iklim dipengaruhi oleh unsur: temperatur tekanan,
kelembaban, angin, awan, dan curah hujan. Pengertian cuaca adalah rata-rata
udara di suatu tempat uang terbatas dan relatif sempit, sedangkan Iklim adalah
keadaan rata cuaca di satu daerah yang cukup luas dan dalam kurun waktu yang
cukup lama. Iklim dunia dikelompokan berdasarkan berdasarkan garis lintang
dan garis bujur serta suhu. Jenis iklim dunia sebagai berikut : Iklim Dingin, Iklim
Pegunungan, Iklim Artik Kutub, Iklim Sedang Dingin, Iklim Gurun.
B. Klasifikasi Iklim
Berdasarkan letak astronomis dan ketinggian tempat, iklim terbagi
menjadi dua yaitu iklim matahari dan iklim fisis, sedangkan klasifikasi iklim
menurut para ahli sebagai berikut : 1. Iklim Matahari; 2. Iklim Koppen; 3. Iklim
Schamidt - Ferguson; 4. Iklim Oldman; 5. Iklim Yunghunh

105
1. Iklim Matahari
Iklim matahari yaitu iklim yang didasarkan atas perbedaan panas
matahari yang diterima permukaan bumi. Daerah-daerah yang berada pada
lintang tinggi lebih sedikit memperoleh sinar matahari, sedangkan daerah yang
terletak pada lintang rendah lebih banyak menerima sinar matahari,
berdasarkan iklim matahari terbagi menjadi: iklim tropik; iklim sub tropik; iklim
sedang dan iklim dingin.
2. Iklim Koppen
Wladimir Koppen seorang ahli berkebangsaan Jerman membagi iklim
berdasarkan curah hujan dan temperatur menjadi lima tipe iklim :
Gambar : Iklim Koppen

106
a. Iklim A, yaitu iklim hujan tropis, dengan ciri temperatur bulanan rata-
rata lebih dari 18 oC, suhu tahunan 20 oC – 25 oC dengan curah hujan
bulanan lebih dari 60 mm.
b. Iklim B, yaitu iklim kering/gurun dengan ciri curah hujan lebih kecil
daripada penguapan, daerah ini terbagi menjadi Iklim stepa dan gurun.
c. Iklim C, yaitu iklim sedang basah engan ciri temperatur bulan terdingin
-3oC-18oC, daerah ini terbagai menjadi: Cs (iklim sedang laut dengan
musim panas yang kering) Cw (iklim sedang laut dengan musim dingin
yang kering) Cf (iklim sedang darat dengan hujan dalam semua bulan)
d. Iklim D, yaitu iklim dingin dengan ciri temperatur bulan terdingin kurang
dari 3oC dan temperatur bulan terpanas lebih dari 10oC, daerah ini
terbagi menjadi Dw, Df
1) Dw adalah iklim sedang (darat) dengan musim dingin yang kering
2) Df adalah iklim sedang (darat) dengan musim dingin yang lembab.
e. Iklim E, yaitu iklim kutub. Dengan ciri bulan terpanas temperaturnya
kurang dari 10 oC Daerah ini terbagi menjadi :
1) ET Iklim tundra
2) DF Iklim salju
3. Iklim Schamidt - Ferguson
Schmidt dan Ferguson membagi iklim berdasarkan banyaknya curah
hujan pada tiap bulan yang dirumuskan sebagai berikut :
Di Indonesia terbagi menjadi 8 tipe Iklim :
A. kategori sangat basah, nilai Q = 0 - 14,3 %
B. kategori basah, nilai Q = 14,3 � 33,3 %
C. kategori agak basah nilai Q 33,3 � 60 %

107
D. kategori sedang, nilai Q = 60 � 100 %
E. kategori agak kering, nilai Q = 100 � 167 %
F. kategori kering, nilai Q = 167 � 300 %
G. kategori sangat kering, nilai Q = 300 � 700 %
H. kategori luar biasa kering, nilai Q = lebih dari 700 %
Jadi kota X beriklim B. Langkah masukan dalam grafik.
Curah hujan Kota X 1998-2000
Bulan 1998 1999 2000 Jml Rata-rata Januari 343 345 310 Pebruari 360 260 245 Maret 200 275 175 April 150 184 120 Mei 100* 93* 30* Juni 75* 60* 0* Juli 50* 44* 0* Agustus 40** 112 84* September 112 153 125 Oktober 225 244 200 Nopember 280 275 275 Desember 310 322 350 JBB 8 9 8 25 8,33 JBK 2 1 3 6 2,0 JBL 2 2 1 5 1,67

108
4. Iklim Oldeman
Oldeman membagi iklim menjadi 5 tipe iklim yaitu :
a. Iklim A. Iklim yang memiliki bulan basah lebih dari 9 kali berturut-turut
b. Iklim B. Iklim yang memiliki bulan basah 7-9 kali berturut-turut
c. Iklim C. Iklim yang memiliki bulan basah 5-6 kali berturut-turut
d. Iklim D. Iklim yang memiliki bulan basah 3-4 kali berturut-turut
Berdasarkan urutan bulan basah dan kering dengan ketententuan
tertentu diurutkan sebagai berikut: a) Bulan basah bila curah hujan lebih dari
200 mm; b) Bulan lembab bila curah hujan 100 – 200 mm; c) Bulan kering bila
curah hujan kurang dari 100 mm.
A : Jika terdapat lebih dari 9 bulan basah berurutan.
B : Jika terdapat 7 � 9 bulan basah berurutan.
C : Jika terdapat 5 � 6 bulan basah berurutan.
D : Jika terdapat 3 � 4 bulan basah berurutan.
E : Jika terdapat kurang dari 3 bulan basah berurutan.
Pada dasarnya Kriteria bulan basah dan bulan kering yang dipakai
Oldeman berbeda dengan yang digunakan oleh Koppen atau pun Schmidt
Ferguson Bulan basah yang digunakan Oldeman adalah sebagai berikut: Bulan
basah apabila curah hujan lebih dari 200 mm. Bulan lembab apabila curah
hujannya 100 - 200 mm. Bulan kering apabila curah hujannya kurang dari 100
mm.
5. Iklim Yunghunh
Pembagian iklim didasarkan pada ketinggian tempat yang ditandai
dengan jenis vegetasi, zone iklimnya adalah terbagi lima zone:

109
Gambar : Iklim Yunghunh
a. Zone iklim panas. Ketinggian 0 � 700 m, suhu rata-rata tahunan lebih
220C ( padi, jagung, tebu dan kelapa).
b. Zone iklim sedang.Ketinggian 700-1500m, suhu rata-rata tahunan antara
15 � 220C ( kopi, the, kina dan karet).
c. Zone iklim sejuk.Ketinggian.1500 � 2500, suhu rata-rata tahunan 110C
� 15 0C (cocok tanaman holtikultura).
d. Zone iklim dingin.Ketinggian 2500 � 400m, dengan suhu rata-rata
tahunan 110C (zone ini tumbuhan yang ada berupa lumut).
e. Zone iklim salju tropis. Ketinggian lebih dari 400m dari permukaan laut,
di daerah ini tidak terdapat tumbuhan.

110
DAFTAR PUSTAKA
BUKU:
A. Baiquni. 1990. Filsafat Fisika dan al-Qur’an. “Ulumul Qur’an, no.4. Jakarta.
Bambang Suhendro. 1994. Bencana Tsunami dan Upaya Penang-gulangannya.
UNISIA, No. 23 Tahun XIV Triwulan 3. Bintarto. 2000. Suatu Tijauan Filsafat Geografi. Seminar Peningkatan Relevansi
MetodePenelitian Geografi. Fakultas Geogari UGM. Yogyakarta. Campbell, N.A.,J.B. Reece & L.G. Mitchell. 1999. Biology Fifth Edition.(alih bahasa
Wasmen Manalu). Benjamin Cummings, Menlo Park.
Echer, E.G. 1980. On A Clasification Of Central Eruption According To Gas Pressure Of The Magma And Viscosity Of The Lavas. Leiden: Geol Meided.
Kimball, J.W. 1975. Man and Nature. Principles of Human and Environmental
Biology. Addison-Wesley, Reading, Mass.
Soeriaatmadja. 1997. Ilmu Lingkungan. Bandung: ITB.
INTERNET:
http://www.edukasi.net http://www.ayocintabumi.110mb.com/sampah.html http://afand.cybermq.com/post/detail/2405/linkungan-hidup-kerusakan-lingkungan-pengertian-kerusakan-lingkungan-dan-pelestarian-
http://www.crayonpedia.org/mw/BSE:Lingkungan_Hidup_dan_Pelestariannya_8.1_(BAB_3)