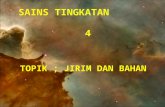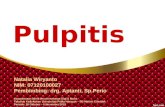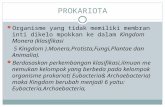Bab 4
-
Upload
tommymulyadin -
Category
Documents
-
view
8 -
download
2
Transcript of Bab 4

PT. MUARA CONSULT
BAB IV METODOLOGI TEKNIS DAN PENDEKATAN POTENSI GEMPABUMI DAN TSUNAMI DALAM MITIGASI BENCANA ALAM WILAYAH KECAMATAN CIKAKAK KABUPATEN SUKABUMI
4.1 Metodologi Teknis Analisa dan Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penyelesaian pekerjaan terdiri atas data sekunder
dan data primer. Data sekunder diperoleh dari arsip, catatan, dokumen dan
informasi yang ada di Bappeda, BPS, Dinas Pertanian, BPS serta instansi lain
yang terkait dengan tujuan penelitian dan dikumpulkan dengan cara studi
kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survey, yaitu survey
data institusional untuk memperoleh data sekunder dan peta wilayah serta data
laporan kajian-kajian penting yang berhubungan dengan pengembangan
wilayah perdesaan, beserta hasil studi dan kebijakan yang terkait. Teknik
pengumpulan data lainnya dilakukan dengan wawancara untuk memperoleh
data primer, Wawancara (pengumpulan data primer) dengan aparat
pemerintah instansi terkait tokoh masyarakat dan responden lainnya yang
diperlukan dalam kajian ini.
Teknik pengumpulan data lain adalah berupa rekaman keadaan lapangan
secara visualisasi dengan menggunakan alat perekam baik berupa kamera foto
maupun video kamera sebagai bagian dari perjalanan survey untuk
mendukung/memperkuat hasil kajian lapangan yang berupa data atau
informasi lainnya.
| LAPORAN AKHIR IV-56

PT. MUARA CONSULT
Gambar 4.1 Diagram Penataan Kawasan Pemukiman Dalam Kaitan Mitigasi
Bencana Alam
4.1.1 Pemetaan Resiko Bencana
Pemetaan Resiko bencana didasarkan pada tiga komponen, yaitu Ancaman
(hazard), Kerentanan (vulnerability) dan Kapasitas (capacity). Formula dasar
yang digunakan untuk menentukan Resiko bencana adalah menurut Winaryo
(2007) sebagai berikut:
Berdasarkan formulasi tersebut diketahui ada 3 (tiga) komponen utama dalam
penyusunan peta Resiko yaitu ancaman (H), kerentanan (V), dan kapasitas (C).
| LAPORAN AKHIR IV-57
Tujuan Studi
Kajian Literatur
Kajian Lapangan 5 Propinsi
Konsep Pengelolaan Bencana
Jenis Bencana
Penyebab dan Mekanisme Kerusakan
Bentuk-bentuk Pengurangan Risiko Bencana
Kelembagaan Pengelolaan
Partisipasi Masyarakat
Konsep dan Pedoman Penataan Kawasan Permukiman
Tindak Mitigasi untuk Kawasan Permukiman
Pedoman Penataan Kawasan Permukiman Dalam Rangka Mitigasi
Bencana
Konsep Pedoman Penataan Kawasan
Permukiman
Kajian Materi Bidang Penataan Kawasan Permukiman Dalam Rangka Mitigasi Bencana

PT. MUARA CONSULT
Dalam penyusunannya pemetaan Resiko ini menggunakan 3 (tiga) kelas skoring
dan metode pembobotan untuk masing-masing parameter. Nilai Resiko akhir
didasarkan operasi fungsi dalam formula tersebut dengan menggunakan nilai
total masing-masing komponen. Berikut ini akan diuraikan secara singkat
masing – masing komponen penyusunan peta Resiko.
4.1.2 Pemetaan Daerah Ancaman
Berdasarkan UU No. 24/2007 ttg Penanggulangan Bencana, Pasal 1, Ayat 2
pengertian ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa
menimbulkan bencana. Ancaman merupakan salah satu faktor yang paling
mempengaruhi Resiko bencana di suatu daerah.
Penentuan tingkat ancaman dilakukan dengan menggunakan skor, dimana
semakin besar nilai skor maka semakin tinggi tingkat ancamannya. Selain itu
juga dilakukan pembobotan untuk setiap parameter pada setiap jenis bencana.
Parameter yang lebih berpengaruh terhadap potensi terjadinya suatu bencana
akan mendapat bobot lebih besar daripada parameter yang kurang
berpengaruh. Setiap jenis bencana mempunyai parameter berbeda sesuai
relevansinya. Berikut ini dijelaskan metode pemetaan setiap jenis bencana,
parameter – parameter penyusunnya dan sistem penilaiannya (bobot dan skor).
Mengacu pada pasal 1 ayat 2 UU No. 24/2007, paling tidak terdapat ada 5
(lima) jenis potensi bencana alam yang bisa terjadi di wilayah Kabupaten
Sukabumi. Bencana alam tersebut adalah :
1) Erupsi Gunungapi
2) Angin Ribut/Putting Beliung dan
3) Gempabumi
4) Tsunami
5) Gerakan Tanah/ Longsoran
4.1.2.1 Erupsi Gunungapi
Dit. Vulkanologi Dan Mitigasi Bencana Gunungapi telah membuat peta ancaman
erupsi Gunung api (termasuk G. Gede yang terdekat dengan wilayah
Sukabumi) , meliputi tiga kawasan bahaya sebagai berikut:
| LAPORAN AKHIR IV-58

PT. MUARA CONSULT
1) Daerah Kawasan Rawan Bencana III, merupakan daerah yang
letaknya terdekat dengan sumber bahaya, dalam hal ini titik letusan di
daerah puncak atau kawah utama, sehingga kemungkinan untuk dilanda
oleh bahaya aliran seperti aliran lava, awan panas dan aliran lahar
letusan, sangat besar.
2) Daerah Kawasan Rawan Bencana II, merupakan daerah lontaran dan
daerah bahaya terhadap lahar hujan. Dengan perkiraan lontaran kira-kira
5 km dari pusat letusan, kecuali pada aliran yang curam akan lebih 5 km
dan topografinya tinggi akan kurang dari 5 km tergantung keadaan
lapangan.
3) Daerah Kawasan Rawan Bencana I, merupakan daerah yang
kemungkinan akan terlanda lahar, daerah ini meliputi tempat-tempat
sepanjang lembah sungai berhulu di sekitar puncak kemungkinannya akan
lebih besar dilalui lahar.
4.1.2.2 Angin Ribut
Pemetaan ancaman angin ribut merupakan salah satu jenis pemetaan yang sulit
dilakukan. Hal ini dikarenakan ketiga jenis bencana tersebut merupakan jenis
bencana yang bersifat kontinu atau dapat terjadi di mana saja.
Oleh karena itu, untuk skala kabupaten jenis bencana alam ini tidak dilakukan
pada tingkat akurasi dan presisi pemetaan yang tinggi (yang hanya dapat
diselesaikan dengan pemodelan fisik/dinamik), dipilih metode ploting. Ploting
yang dimaksud adalah setiap kejadian bencana yang pernah terjadi di suatu
daerah diplotkan ke dalam peta.
Frekuensi kejadian bencana yang pernah terjadi kemudian dijadikan acuan
untuk menentukan tingkat ancaman bencana bagi daerah terkait. Sistem
klasifikasi yang digunakan sama dengan klasifikasi untuk bencana lain, yaitu
klasifikasi aritmatik tiga kelas .
4.1.2.3 Gempabumi
Penentuan ancaman gempabumi didasarkan pada tiga komponen yaitu; jalur
patahan, keberadaan sungai dan tingkat kerusakan infrastruktur. Ke tiga
| LAPORAN AKHIR IV-59

PT. MUARA CONSULT
parameter tersebut dianggap mempunyai pengaruh sama, oleh karena itu
bobotnya sama.
Pemetaan ini menggunakan asumsi bahwa potensi gempabumi ditentukan
berdasarkan jarak dari lokasi patahan (sebagai pemicu gempa), oleh karena itu
metode yang digunakan adalah analisis buffer. Jika suatu daerah berada dalam
radius 500 meter dari jalur patahan, maka ancaman gempanya termasuk dalam
kategori tinggi. Sedangkan jika berada dalam radius lebih dari 500 meter namun
kurang dari 1000 meter, potensi ancamannya termasuk kategori sedang dan jika
jaraknya lebih dari 1000 meter, maka potensi ancaman gempanya rendah.
Asumsi dan metode yang sama juga berlaku untuk sungai yang terbentuk akibat
patahan dan mengalir di sepanjang jalur patahan, sehingga diperlakukan sama
dengan jalur patahan.
Gambar 4.2 Diagram Alir Peta Rawan Gempabumi
4.1.2.4 Bencana Tsunami
Diketahui bahwa banyak sumber gempabumi di selatan P.Jawa berada di dasar
lautan dan memiliki potensi bisa menibulkan gelombang tsunami yang tidak
| LAPORAN AKHIR IV-60

PT. MUARA CONSULT
saja menghantam pesisir pantai di sekitar sumber gempa tetapi juga mencapai
beberapa km ke daratan. Dari sejarah kegempaan, secara umum untuk
Sukabumi dan khususnya Cikakak, belum pernah terjadi tsunami.
Perilaku kerusakan pada lokasi terjadinya gempabumi yang sumbernya di
bawah laut potensi tsunami diketahui disebut dengan intensitas kerusakan
gempabumi dan untuk menilai kerusakan yang dihasilkan dalam kaitan
pengaruh pada benda-benda, bangunan, dan tanah, dan akibatnya pada orang-
orang dan dinyatakan dalam skala nilai kerusakan dari 1 s/d 12). Dan skala
tersebut adalah MMI (Modified Mercalli Intensity) diperkenalkan oleh
Giuseppe Mercalli pada tahun 1902. Magnituda adalah parameter gempa yang
diukur berdasarkan yang terjadi pada daerah tertentu, akibat goncangan gempa
pada sumbernya.
Satuan yang digunakan adalah Skala Richter. Skala ini diperkenalkan oleh
Charles F. Richter tahun 1934. Sebagai contoh, gempabumi dengan kekuatan 8
Skala Richter setara kekuatan bahan peledak TNT seberat 1 Gigaton atau 1
milyar ton.
4.1.2.5 Tanah Longsor
Parameter penyusun ancaman gerakan tanah/tanah longsor terdiri dari kondisi
geologi; litologi, bentuk lahan, kemiringan lereng dan tutupan vegetasi. Bentuk
lahan merupakan elemen paling berpengaruh, oleh karena itu memperoleh
bobot paling tinggi. Litologi dan kemiringan lereng dianggap mempunyai
pengaruh yang sama, oleh karena itu diberi bobot yang sama (20).
Sistem penilaian untuk bencana tanah longsor sama dengan pemetaan banjir.
Skor setiap entitas pada setiap parameter dikalikan dengan bobot kemudian
semua parameter ditumpangsusunkan dan dijumlah total skornya.
| LAPORAN AKHIR IV-61

PT. MUARA CONSULT
Gambar 4.3 Diagram Alir Peta Bencana Tanah Longsor
4.1.3 Peta Resiko (Risk)
Resiko bencana dapat diketahui dari hubungan antara ancaman, kerentanan
dan kapasitas bencana. Resiko bencana diperoleh dari hasil formulasi total
skor untuk ancaman, kerentanan dan kapasitas dengan menggunakan rumus
berikut (Winaryo,2007).
Nilai Resiko yang diperoleh kemudian dibuat klasifikasi menjadi tiga secara
aritmatik (rendah, sedang, tinggi) untuk mengetahui tingkat Resiko bencana
setiap desa.
4.1.3.1 Skoring Peta Ancaman
Sebagaimana telah diuraikan pada metode pemetaan ancaman bencana untuk
setiap jenis bencana peta tematik ancaman bencana alam di wilayah Kecamatan
Cikakak, Kabupaten Sukabumi dibagi menjadi tiga kelas.
Peta – peta ancaman kemudian akan ditumpangsusunkan (overlay)dengan peta
kerentanan dan kapasitas untuk mengetahui tingkat Resiko bencana. Untuk
menentukan tingkat Resiko bencana berdasarkan informasi ancaman,
| LAPORAN AKHIR IV-62

PT. MUARA CONSULT
kerentanan dan kapasitas, digunakan sistem skoring. Total skor yang tinggi
mengindikasikan Resiko bencana yang tinggi, demikian pula sebaliknya.
| LAPORAN AKHIR IV-63

PT. MUARA CONSULT
Gambar 4.4 Peta Wilayah Ancaman Kecamatan Cikakak
4.1.3.2 Kerentanan (Vulnerability)
Kerentanan adalah kondisi atau karakteristik biologis, geografis, sosial,
ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk
jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan masyarakat tersebut dalam
mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan menanggapi dampak bahaya
tertentu.
Dalam metode pemetaan Resiko ini data kerentanan yang digunakan adalah
pada tingkat kecamatan, hal ini dengan pertimbangan skala dan cakupan
wilayah pemetaan adalah tingkat provinsi. Sedangkan tingkat desa digunakan
untuk wilayah kabupaten/kota.
Sumber data yang digunakan adalah data PODES, SUSENAS, Kecamatan dalam
angka, data – data bencana pemerintah dan data – data infrastruktur dari
dinas/instansi terkait.
Komponen kerentanan yang digunakan dalam metode ini meliputi komponen
fisik, demografi, ekonomi dan lingkungan. Berikut ini akan diuraikan masing-
masing komponen.
| LAPORAN AKHIR IV-64

PT. MUARA CONSULT
1) Komponen Fisik
Komponen fisik merupakan komponen kerentanan berupa fisik benda yang dapat
hilang atau rusak apabila terkena ancaman. Komponen ini merupakan fisik
benda yang dianggap memiliki nilai. Dalam pemetaan ini komponen fisik terdiri
dari 2 (dua) indikator yaitu kepadatan bangunan dan jumlah industri.
Kepadatan bangunan merupakan cerminan keberadaan penduduk, selain juga
nilai bangunan itu sendiri. Kepadatan bangunan yang tinggi menngindikasikan
jumlah penduduk yang banyak dan nilai ekonomi bangunan yang besar,
sehingga jika terjadi bencana akan dapat menyebabkan Resiko yang tinggi.
Demikian pula dengan jumlah industri yang mencerminkan adanya kegiatan
penduduk, fungsi/nilai infrastruktur dan nilai ekonomi barang/jasa.
Data yang diperoleh bersumber dari data PODES,SUSENAS. dan informasi
penggunaan lahan dari Peta Rupabumi Indonesia Skala 1 : 25.000
BAKOSURTANAL.
Tabel 4.1 Indikator Kerentanan Fisik
Seperti halnya dengan paramater lain, data – data komponen fisik dari pameter
kerentanan juga dibagi menjadi tiga kelas dengan sistem skoring sebagaimana
di atas.
Sistem klasifikasi untuk menentukan kelas jarang, sedang, padat untuk
parameter kepadatan bangunan dan kecil, sedang, besar untuk industri,
menggunakan klasifikasi aritmatik.
2) Komponen Demografi
Komponen ini berupa data yang terkait dengan kependudukan yang dinilai
rentan apabila terkena ancaman, indikator yang digunakan dalam komponen
demografi meliputi kepadatan penduduk dan tingkat kemiskinan.
| LAPORAN AKHIR IV-65

PT. MUARA CONSULT
Kepadatan penduduk menggunakan satuan jiwa/km2, sedangkan tingkat
kemiskinan menggunakan data jumlah penduduk miskin yang dinilai dalam
bentuk persentase dari total jumlah penduduk untuk kecamatan yang
bersangkutan.
Klasifikasi untuk menentukan miskin, menengah, kaya dan untuk jarang, sedang,
padat digunakan klasifikasi aritmatik.
Tabel 4.2 Indikator Kerentanan Demografi
3) Komponen Ekonomi
Komponen ini terkait dengan sumberdaya ekonomi yang dimiliki penduduk.
penilaiannya adalah apakah sumber daya yang mereka miliki saat ini akan
terganggu apabila terkena bencana. Indikator yang digunakan dalam komponen
ini adalah jumlah ternak dan luas lahan tanaman pangan. Klasifikasi untuk
menentukan kecil, sedang, luas untuk parameter jumlah ternak dan tidak luas,
sedang, luas untuk parameter luas lahan pangan menggunakan klasifikasi
aritmatik.
Tabel 4.3 Indikator Kerentanan Ekonomi
4) Peta Kerentanan
Peta kerentanan merupakan hasil tumpangsusun seluruh indikator kerentanan.
Sedangkan untuk penentuan tingkat kerentanan mendasarkan pada total skor
bobot dari seluruh indikator. Skor bobot adalah hasil dari perkalian nilai setiap
indikator dengan bobot, kemudian skor bobot setiap indicator dijumlahkan untuk
memperoleh total skor kerentanan.
| LAPORAN AKHIR IV-66

PT. MUARA CONSULT
Untuk menentukan tingkat kerentanan, Total skor kerentanan diklasifikasikan
menjadi tiga kelas (rendah, sedang, tinggi) dengan menggunakan klasifikasi
aritmatik.
Nilai bobot indicator = (Nilai indikator x bobot indikator)
Nilai Kerentanan Total = Nilai bobot indikator A + Nilai bobot
indikator B + ……… dst
| LAPORAN AKHIR IV-67

PT. MUARA CONSULT
Gambar 4.5 Peta Rawan Bencana Alam Kecamatan Cikakak
| LAPORAN AKHIR IV-68

PT. MUARA CONSULT
4.1.3.3 Kapasitas (Capacity)
Kemampuan/kapasitas adalah sumber daya, cara dan kekuatan yang dimiliki
masyarakat agar memungkinkan masyarakat dapat mempertahankan dan
mempersiapkan diri, mencegah, menanggulangi, meredam serta dengan cepat
memulihkan diri akibat bencana.
Kapasitas merupakan komponen yang dinamis dan paling memungkinkan untuk
dikelola dalam mengurangi Resiko bencana. Ancaman bencana, terutama untuk
bencana alam merupakan faktor permanen yang sulit diubah karena merupakan
pengaruh dari aspek fisik wilayah.
Sedangkan kerentanan dapat diubah, namun memerlukan usaha dan dana yang
tidak sedikit. Kendala yang dihadapi pun biasanya banyak dan kompleks karena
melibatkan budaya masyarakat.
Sebagaimana dengan kerentanan, kapasitas bencana dalam metode ini
dipetakan menurut satuan kecamatan. Sumber data yang digunakan antara lain
data SUSENAS, PODES, data infrastruktur dari PU dan data – data kebencanaan
yang ada di BAPEDA. Ada dua komponen kapasitas/kemampuan yang digunakan
dalam metode ini yaitu komponen struktur fisik dan sosial.
1) Komponen Struktur Fisik
Komponen ini merupakan sumberdaya yang dimiliki masyarakat dalam wujud
fisik kebendaan yang mampu digunakan untuk mengurangi dan melindungi
masyarakat dari akibat bencana. Indikator komponen ini meliputi antara lain
adanya fasilitas kesehatan, jalur evakuasi, rambu-rambu tanda bahaya, sistem
peringatan dini, jaringan telekomunikasi, TV dan radio, Jalan raya, bandara,
terminal dan pelabuhan laut. Berikut ini adalah daftar indikator dan sistem skor
dan pembobotannya.
| LAPORAN AKHIR IV-69

PT. MUARA CONSULT
Tabel 4.4 Indikator Kapasitas Fisik
2) Komponen Sosial
Komponen sosial merupakan wujud sikap, pengetahuan dan kesadaran
masyarakat terhadap bencana. Masyarakat yang sadar bencana dan memiliki
pengetahuan kebencanaan akan memiliki kemampuan untuk melakukan
antisipasi dan mitigasi bencana baik secara terstruktur maupun mandiri,
sehingga dapat mengurangi Resiko jika terjadi bencana. indikator komponen
sosial yang digunakan dalam metode ini yaitu ada atau tidaknya
lembaga/organisasi penanggulangan bencana di tiap kecamatan dan frekuensi
kegiatan pendidikan/pelatihan penanggulangan bencana.
Tabel 4.5 Indikator Kapasitas Sosial
| LAPORAN AKHIR IV-70

PT. MUARA CONSULT
3) Kapasitas
Peta kapasitas diperoleh dari hasil tumpangsusun seluruh indikator kapasitas,
dan jumlah dari nilai bobot indikator. Dari nilai total dilakukan pengklasifikasian
nilai kapasitas secara aritmatik menjadi 3 kelas, yaitu tinggi, sedang, dan
rendah.
4.2 Kecamatan Cikakak Sebagai Daerah Berpotensi Bencana
Gempabumi
4.2.1 Kapasitas Bencana Gempabumi
1) Gempabumi merupakan kejadian alam yang belum dapat diperhitungkan
dan diperkirakan secara akurat baik kapan dan dimana terjadinya serta
magnitudanya.
2) Penentuan ancaman gempabumi didasarkan pada tiga komponen yaitu;
jalur patahan, keberadaan sungai dan tingkat kerusakan infrastruktur.
Ketiga parameter tersebut dianggap mempunyai pengaruh sama, oleh
karena itu di dalam penghitungan resiko gempa diberikan bobot sama.
3) Karena tidak dapat dicegah dan tidak dapat diperkirakan secara akurat,
usaha-usaha yang biasa dilakukan adalah menghindari wilayah dimana
terdapat fault rupture, kemungkinan tsunami, dan landslide Serta
bangunan sipil harus direncanakan dan dibangun tahan gempa.
4.2.2 Potensi Korban dan Kerugian Terkait Potensi Kegempaan di
daerah Cikakak – Sukabumi
1) Kerusakan tidak langsung pada tanah yang menyebabkan terjadinya
likuifaksi, cyclic mobility, lateral spreading, kelongsoran lereng,
keretakan tanah, subsidence, dan deformasi yang berlebihan, serta
2) Kerusakan struktur sebagai akibat langsung dari gaya inersia yang
diterima bangunan selama goncangan. Pencegahan kerusakan struktur
sebagai akibat langsung dari gaya inersia akibat gerakan tanah dapat
dilakukan melalui proses perencanaan dengan memperhitungkan suatu
tingkat beban gempa rencana.
| LAPORAN AKHIR IV-71

PT. MUARA CONSULT
Oleh karena itu, dalam perencanaan infrastruktur tahan gempa, analisis dan
pemilihan parameter pergerakan tanah mutlak diperlukan untuk mendapatkan
beban gempa rencana. Secara umum, dalam perencanaan infrastruktur tahan
gempa, terdapat beberapa jenis metoda analisis dengan tingkat kesulitan dan
akurasi yang bervariasi.
Sesuai dengan metoda analisis yang digunakan, parameter pergerakan tanah
yang diperlukan untuk perhitungan dapat diwakili oleh:
1. percepatan tanah maksimum,
2. respon spektra gempa, dan
3. riwayat waktu percepatan gempa (time histories).
| LAPORAN AKHIR IV-72

PT. MUARA CONSULT
Gambar 4.6 Peta Mitigasi Bencana Alam Kecamatan Cikakak
4.2.3 Pencegahan dan usaha Sosialisasi Bencana Gempa
Untuk mencegah timbulnya korban manusia dan kerugian material akibat
gempabumi, maka perlu dilakukan sosialisasi secara menerus dan
berkesinambungan bisa melalui poster, spanduk, ataupun pesan-pesan singkat.
Baik langsung maupun tidak langsung. kepada masyarakat.
Untuk bencana alam tsunami yang penyebabnya juga gempabumi di laut, dan
mengakibatkan gelombang pasang, maka penjelasan perlu dilakukan di pesisir
laut dalam hal ini Kecamatan Cikakak yang dalam pengembangan daerah
diproyeksikan ke dalam daerah wisata maka perlu dilakukan tindakan
peringatan darurat
1. bila akan mendirikan bangunan di tepi pantai, hendaknya diberi sarana
untuk mengungsi jika terjadi peringatan ada bencana tsunami.
2. Perlu ada jalan evakuasi ke tempat yang lebih tinggi, dimana untuk Cikakak
telah dipersiapkan 2 (dua) jalur jalan menuju tempat datar dan memiliki
beda tinggi lebih dari 40 meter.dari muka laut. Yang dapat dicapai dalam
kurun waktu 10 menit.
3. Fasilitas evakuasi tsunami, perlu dipersiapkan ada sarana mck, sanitasi dan
kelengkapan perumahan/bangunan terbangun untuk kondisi darurat.
| LAPORAN AKHIR IV-73

PT. MUARA CONSULT
4.3 Wilayah Potensi terjadi fault rupture, kemungkinan tsunami, dan
landslide untuk Kecamatan Cikakak- Kabupaten Sukabumi
Karena tidak dapat dicegah dan tidak dapat diperkirakan secara akurat, usaha-
usaha yang biasa dilakukan adalah menghindari wilayah dimana terdapat fault
rupture, kemungkinan tsunami, dan landslide . Bangunan sipil harus
direncanakan dan dibangun tahan gempa :
4.3.1 Wilayah Potensi Terjadi Fault Rupture
Berdasar peta geologi daerah kecamatan Cikakak tidak dijumpai adanya jaur
patahan . Patahan dan struktur perlipatan hadir di beberapa daerah di bagian
tenggara Ds.Gandasuli memiliki potensi Fault Rupture , dimana berdasarkan
kondisi struktur geologi merupakan zona patahan, yaitu daerah bagian tenggara
Kecamatan Cikakak, atau sekitar Gandasuli.
Diketahui daerah tersebut dibentuk oleh batuan sedimen Tersier yang
membentuk antiklin-sinklin dan tersesarkan oleh patahan mendatar mengiri.
(Peta geologi daerah Cikakak.
Pergerakan lapisan batuan yang dipacu oleh tutupan soil yang berasal dari
lapukan breksi hasil gunungapi, telah menyebabkan terjadinya
longsoran/gerakan tanah dan bersamaan dengan terjadinya gempa 2006.
4.3.2 Wilayah Potensi Terjadi Tsunami Kecamatan Cikakak
Dari hasil analisiis potensi dan kendala pengembangan kawasan dengan asumsi
kriteria dan tolok ukur yang dipakai, maka dapat dilakukan deliniasi penentuan
batas wilayah yang memiliki potensi tsunami dengan analisis overlay /
superimposed pada peta dasar skala 1 : 25.000. setelah dilakukan penghitungan
luas daerah, maka didapat luasan wilayah Kecamatan Cikakak sekitar 12.091
Ha. Sementara daerah yang berpotensi adalah berkisar 10% atau hampir
mencapai 12 Ha.
Kecamatan Cikakak tersebut kawasan berpotensi tsunami adalah di pesisir
dibatasi oleh kaki perbukitan, pesisir pantai, kemiringan lereng yang membatasi
ketentuan daerah terbangun, serta batas pesisir laut dan sungai memperlihatkan
ciri-ciri sebagai berikut .
| LAPORAN AKHIR IV-74

PT. MUARA CONSULT
4.3.2.1 Ciri Fisik
Dilihat dari aspek fisik, maka wilayah berpotensi tsunami tersebut mempunyai
ciri-ciri:
1) Menempati kawasan pinggiran pantai, berupa dataran dengan beda tinggi
kurang dari 30 meter terhadap tinggi muka airlaut, ditempati oleh aluvial
pantai yang terdiri atas material berukuran pasir, keikil, kerakal dan
berangkal dengan kisaran diameter butir Ф + 0.01 mm s/d 30 cm.
2) Sebagian besar merupakan tempat permukiman penduduk khususnya
nelayan dan lokasi wisata, ada beberapa bangunan hotel, wisma, tempat
penginapan dan rumah sakit. yang merupakan satu kesatuan dengan luas,
jumlah bangunan, kepadatan bangunan yang relatif lebih tinggi daripada
desa lain di Kecamatan Cikakak
3) Proporsi bangunan permanen lebih besar di tempat itu daripada di
wilayah-wilayah desa disekitarnya.
4) Dijumpai lebih banyak bangunan fasilitas sosial-ekonomi (sekolah,
poliklinik, toko, kantor pemerintahan, dan lain-lain) daripada wilayah
sekitarnya.
4.3.2.2 Ciri Sosial Ekonomi
Dilihat dari aspek-aspek sosial ekonomi, maka wilayah kota mempunyai ciri-ciri:
1) Mempunyai jumlah penduduk relatif lebih besar daripada wilayah desa
sekitarnya, walaupun bukan penduduk menetap, yang dalam satu
kesatuan areal terbangun memiliki fasilitas singgah/tinggal cukup besar .
(> 200 orang) .
2) Mempunyai kepadatan penduduk yang relatif lebih tinggi dari wilayah
desa sekitarnya.
3) Mempunyai proporsi jumlah penduduk yang bekerja di sektor-sektor non
pertanian, seperti: perdagangan, industri wisata, jasa dan lain-lain, yang
lebih tinggi dari wilayah sekitarnya.
| LAPORAN AKHIR IV-75

PT. MUARA CONSULT
4) Mampu memerankan sebagai pusat kegiatan ekonomi yang
menghubungkan kegiatan pertanian wilayah sekitarnya dan tempat
pemasaran bahan baku untuk kegiatan industri/ souvenir.
4.3.2.3 Pemecahan Masalah
Dari penyajian data dan analisis bahwa salahsatu pemecahan masalah tsunami
di Indonesia adalah diwujudkannya sistem peringatan. Sebuah sistem peringatan
dini tsunami adalah merupakan rangkaian sistem kerja yang rumit dan
melibatkan banyak pihak secara internasional, regional, nasional, daerah dan
bermuara di masyarakat.
Apabila gempa tersebut telah memenuhi syarat atau kondisi terjadinya tsunami
maka BMG akan mengeluarkan peringatan awas tsunami. Artinya, gempa
tersebut berpotensi untuk menimbulkan tsunami. Untuk jenis peringatan ini
maka pemerintah mengeluarkan isu evakuasi. Untuk kategori awas tsunami ini,
Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk membunyikan sirine yang
berarti lakukan evakuasi.
Penerapan prinsip ekologi lanskap dalam perancangan kawasan, karena dapat
membantu dalam membantu perancangan, konservasi, manajemen dengan
menggunakan vegetasi lokal, termasuk mangrove dalam meminimalisir bencana
tsunami. Adanya barrier alami pada daerah pantai dapat membantu menjaga
kawasan dari ancaman tsunami.
4.3.3 Wilayah Potensi Gerakan Tanah Kecamatan Cikakak
Deskripsi umum deliniasi topografi Kecamatan Cikakak adalah meliputi
Topografi yang bervariasi, mulai dasari dataran datar sampai bergelombang
rendah (10%), wilayah perbukitan bergelombang sedang (20%) dan wilayah
perbukitan tinggi (70%) yang letaknya diklasifikasikan sebagai berikut:
1) Bagian Selatan: Merupakan daerah pantai yang tinggi permukaannya
adalah antara 0-150 m. Selain itu Cikakak mempunyai pantai yang curam
dengan ketinggian sekitar 150-300 m.
| LAPORAN AKHIR IV-76

PT. MUARA CONSULT
2) Bagian Utara: Bervariasi mulai dari 150 m hingga yang tertinggi 2000 m.
Ketinggian ini kontinyu sampai kearah utara. Pola bentang alam dan
topografi kecamatan ini dapat dilihat dalam peta kemiringan lereng.
Sebagian besar wilayah ditempati oleh pelapukan batuan volkanik ; breksi, tuf
dan sebagian di Pelabuhanratu ada, pelapukan lava. Pada beberapa lokasi
memperlihatkan adanya potensi gerakan tanah. Dengan tipe Rock Fall /runtuhan
Batu atau jatuhan.
Bencana gerakan tanah sebagai akibat adanya getaran/gempabumi, diketahui
ada beberapa bagian daerah di Kecamatan Ckakak – Kabupaten Sukabumi yang
rentan terhadap bencanaalam geologi gerakan Tanah /Longsor.
Untuk kondisi ini perlu dilakukan beberapa tindakan yakni tindakan kajian
umum yang meliputi Pemetaan lapangan, Penyelidikan untuk mencarai
penyebab dan data dasar untuk penanggulangannya dan selanutnya melakukan
pemeriksaan untuk memastikan penyebab dan metoda penanggulanngannya
atau terdiri atas :
Pemetaan, menyajikan informasi visual tentang tingkat kerawanan
bencana alam geologi di suatu wilayah, sebagai masukan kepada
masyarakat dan atau pemerintah kabupaten/kota dan provinsi sebagai
data dasar untuk melakukan pembangunan wilayah agar terhindar dari
bencana.
Penyelidikan, mempelajari penyebab dan dampak dari suatu bencana
sehingga dapat digunakan dalam perencanaan penanggulangan bencana
dan rencana pengembangan wilayah.
Pemeriksaan, melakukan penyelidikan pada saat dan setelah terjadi
bencana, sehingga dapat diketahui penyebab dan cara penaggulangannya.
| LAPORAN AKHIR IV-77