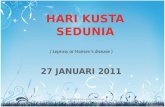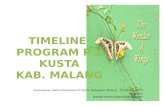BAB 2 kusta
-
Upload
peter-indra-septian -
Category
Documents
-
view
230 -
download
3
description
Transcript of BAB 2 kusta
BAB 2TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan pustaka pada bab ini meliputi konsep dasar penyakit kusta, konsep dasar pengetahuan dan sikap, konsep dasar pendidikan kesehatan, konsep dasar Booklet, dan teori Preceed-Procede.
2.1. Konsep Dasar Penyakit Kusta1. 2. 1. 2.1.1. Definisi KustaKusta atau lepra (leprosy) atau disebut juga Morbus Hansen merupakan penyakit menular kronis yang disebabkan oleh bakteri Mycrobacterium Leprae, melalui kulit dan organ tubuh lain kecuali susunan saraf pusat yang apabila tidak didiagnosis dan diobati secara dini dapat menimbulkan kecacatan (Subdirektorat Kusta dan Frambusia 2007).Penyakit kusta adalah penyakit menular menahun dan disebabkan oleh kuman kusta Mycrobacterium Leprae yang menyerang kulit, saraf tepi, dan jaringan tubuh lain kecuali susunan saraf pusat, untuk mendiagnosisnya dengan mencari kelainan kelainan yang berhubungan dengan saraf tepi dan kelainan-kelainan yang tampak pada kulit (Kemenkes RI 2007).2.1.2. Penyebab KustaM. Leprae atau kuman Hansen adalah kuman penyebab penyakit kusta yang ditemukan oleh sarjana dari Norwegia, GH Armouer Hansen pada tahun 1873. Kuman ini bersifat tahan asam berbentuk batang dengan ukuran 1,8 micron, lebar 0,2-0,5 micron. Biasanya ada yang berkelompok dan data yang tersebar satu-satu, hidup dalam sel terutama jaringan yang bersuhu dingin dan tidak dapat di kultur dalam media buatan.Kuman ini dapat mengakibatkan infeksi sistemik pada binatang armadillo (Kemenkes RI 2007).M. Leprae memiliki dinding yang terdiri dari dua lapisan, yakni lapisan peptidoglikan padat pada bagian dalam dan lapisan transparan lipoposakarida dan kompleks protein-li-poposakarida pada bagian luar. Dinding membrane peptidoglikan tetap simetrik walaupun dilakukan suatu fiksasi dengan pewarnaan, dimana hal tersebut merupakan sifat khas yang tidak didapatkan pada mikrobakterium lainnya (Dali 2003). M.Leprae hidup intraselular dan mempunyai afinitas yang besar pada sel saraf (schwan cell) dan system retikulo endothelial (Prawoto 2008).Masa membelah diri M.Leprae memerlukan waktu 12-21 hari dan masa tunas antara 40 hari sampai dengan 40 tahun. Timbulnya penyakit kusta pada seseorang tidak mudah sehingga tidak perlu ditakuti. Kira-kira 5-15% dari semua penderita kusta dapat menularkan M.leprae, sebagian besar 95% manusia kebal terhadap kusta hanya sebagian kecil yang dapat ditulari(5%), dari sebagian kecil ini (70%) dapat tumbuh sendiri dan hanya 30% yang dapat sembuh sendiri dan hanya 30% yang dapat menjadi sakit kusta (Depkes RI 2005).2.1.3. EpidemiologiPenyebaran penyakit kusta dari suatu benua, negeri dan tempat lain sampai tersebar ke seluruh dunia tampaknya disebabkan oleh perpindahan orang yang telah terkena penyakit tersebut. Masuknya kusta ke pulau-pulau Melanesia termasuk Indonesia diperkirakan terbawa oleh orang-orang Cina (Kosasih 2003). Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan adalah patogenitas kuman penyebab, cara penularan, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan, varian genetik yang berhubungan dengan kerentanan, perubahan-perubahan imunitas, dan kemungkinan-kemungkinan adanya Reservoir diluar manusia (Linuwih 2003).Adapun situasi kusta menurut regional WHO pada awal tahun 2007 (di luar regional Eropa) sebagai berikut.Tabel 2.1 Situasi Kusta menurut Regional WHO pada awal tahun 2007 (di luar regional eropa) (WHO 2007)Regional WHOPrevalensi awal 2007Kasus baru dilaporkan selama tahun 2007
AfrikaAmerikaAsia TenggaraMediterran TimurPasifik Barat40.830 (0,56)32.904 (0,39)133.422 (0,81)4.024 (0,09)8.646 (0,05)42.814 (5,92)41.780 (4,98)201.635 (12,17)3.133 (0,67)7.137 (0,41)
Total219.826296.499
1) Distribusi menurut umurPenyakit kusta jarang sekali ditemukan pada bayi. Angka kejadian penyakit kusta meningkat sesuai umur dengan puncak kejadian pada umur 10-20 tahun (Depkes RI 2006). Penyakit kusta dapat mengenai semua umur dan terbanyak terjadi pada umur 15-29 tahun. Di Brasil terdapat peninggian prevalensi pada usia muda, sedangkan pada penduduk imigran prevalensi meningkat di usia lanjut (Harahap 2000). Menurut Depkes RI (2006), penelitian melaporkan bahwa distribusi penyakit kusta menurut umur berdasarkan prevalensi, hanya sedikit yang berdasarkan insiden karena pada saat timbulnya penyakit sangat sulit diketahui.2) Distribusi menurut jenis kelaminKejadian penyakit kusta pada laki-laki lebih banyak terjadi dari pada wanita, kecuali di Afrika, wanita lebih banyak terkena penyakit kusta dari pada laki-laki (Depkes RI 2006). Menurut Louhennpessy dalam Buletin Penelitian Kesehatan (2007) bahwa perbandingan penyakit kusta pada penderita laki-laki dan perempuan adalah 2,3 : 1,0, artinya penderita kusta pada laki-laki 2,3 kali lebih banyak dibandingkan penderita kusta pada perempuan. Menurut Noor dalam Buletin Penelitian Kesehatan (2007) penderita pria lebih tinggi dari wanita dengan perbandingannya sekitar 2 : 1. Menurut Ress (1975) dalam Zulkifli (2002), dapat ditarik kesimpulan bahwa penularan dan perkembangan penyakit kusta hanya tergantung dari dua hal yakni jumlah atau keganasan Mycobacterium Leprae dan daya tahan tubuh penderita. Disamping itu faktor-faktor yang berperan dalam penularan ini adalah :1. Usia, anak-anak lebih rentan dari pada orang dewasa.2. Jenis kelamin, laki-laki lebih banyak dijangkiti.3. Ras, bangsa Asia dan Afrika lebih banyak dijangkiti.4. Kesadaran sosial, umumnya negara-negara endemis kusta adalah negara dengan tingkat sosial ekonomi rendah.5. Lingkungan, fisik, biologi, sosial, yang kurang sehat. 2.1.4. DiagnosisTanda dan gejala awal biasanya menunjukkan gambaran yang jelas pada stadium yang lanjut dan diagnosis cukup ditegakkan dengan pemeriksaan fisik saja. Penderita kusta adalah seseorang yang menunjukkan gejala klinik kusta dengan atau tanpa pemeriksaan bakteriologik dan memerlukan pengobatan (Dali 2000). Untuk mendiagnosa penyakit kusta perlu dicari kelainan-kelainan yang berhubungan dengan gangguan saraf tepi dan kelainan-kelainan yang tampak pada kulit. Dalam menetapkan diagnosis penyakit kusta perlu mencari tanda-tanda utama atau Cardinal Sign, yaitu :1. Lesi (kelainan) kulit yang mati rasa.Kelainan kulit atau lesi dapat berbentuk bercak keputih-putihan (hypopigmentasi) atau kemerah-merahan (Eritemtous) yang mati rasa (anestesi ).2. Penebalan saraf tepi yang disertai dengan gangguan fungsi saraf.Ganggguan fungsi saraf ini merupakan akibat dari peradangan kronis saraf tepi (neuritis perifer). Gangguan fungsi saraf ini bisa berupa :1) Gangguan fungsi saraf sensoris : mati rasa.2) Gangguan fungsi motoris: kelemahan (parese) atau kelumpuhan/paralise).3) Gangguan fungsi saraf otonom: kulit kering dan retak-retak. 3. Adanya kuman tahan asam didalam kerokan jaringan kulit (BTA+), namun pemeriksaan ini hanya dilakukan pada kasus yang meragukan (Dirjen PP& PL Depkes 2005 ).Menurut Jimmy Wales (2008), tanda-tanda tersangka kusta (Suspek) adalah sebagai berikut:1. Tanda-tanda pada kulit1) Bercak/kelainan kulit yang merah/putih dibagian tubuh2) Kulit mengkilat3) Bercak yang tidak gatal4) Adanya bagian-bagian yang tidak berkeringat atau tidak berambut5) Lepuh tidak nyeri2. Tanda-tanda pada syaraf1) Rasa kesemutan, tertusuk-tusuk dan nyeri pada anggota badan2) Gangguan gerak anggota badan3) Adanya cacat (deformitas)4) Luka (ulkus) yang tidak mau sembuh2.1.5. Klasifikasi KustaDikenal beberapa jenis klasifikasi kusta, sebagian besar didasarkan pada tingkat kekebalan tubuh dan jumlah kuman. Beberapa klasifikasi kusta ini berdasarkan gejala, bakteriologik, hispatologik serta imunologik.2.1.5.1. Klasifikasi Departemen Kesehatan Ditjen P2MPLP dan WHONo.Tanda UtamaPBMB
1. Lesi kulit(macula) datar, papul yang meninggi, nodul1-5 lesiHipopigmentasi/eritemaDistribusi tidak simetrisHilangnya sensasi yang jelas5 lesiDistribusi lebih simetrisHilangnya sensasi
2.Kerusakan saraf (menyebabkan hilangnya sensasi/kelemahan otot yang dipersarafi oleh saraf yang terkena)Hanya satu cabang saraf
BTA (-)Banyak cabang saraf
BTA (+)
Departemen Kesehatan Ditjen P2MPLP dan WHO membagi tipe menjadi tipePause Basiler(PB) danMulti Basiler(MB). Perbedaan kedua tipe ini dapat dilihat pada tabel di bawah (Arif Mansjoer 2000).Tabel 2.2 Klasifikasi/ Tipe Penyakit Kusta Menurut WHOSumber: dikutip dari WHO dalam Arif Mansjoer (2000)
Kelainan kulit dan hasil pemeriksaanPausiBasiler(PB)MultiBasiler(MB)
1.Bercak (Makula) tidak terasa:
1. UkuranKecil dan besarKecil-Kecil
2. DistribusiUnilateral atau bilateral asimetrisBilateral simetris
3. KonsistensiKering dan kasarHalus berkilat
4. BatasTegasKurang tegas
5. Kehilangan rasa pada bercakSelalu ada dan tegasBiasanya tidak jelas, jika ada, terjadi yang sudah lanjut
6. Kehilangan kemampuan berkeringat,rambut rontok pada bercakSelalu ada dan jelasBiasanya tidak jelas, jika ada, terjadi yang sudah lanjut
2.Infiltrat:
a. KulitTidak adaAda, terkadang tidak ada
b. Membran mukosaTidak pernah adaAda, terkadang tidak ada
c. Ciri-ciriCentral healing Punched out lesion Madarosis Ginekomasti Hidung pelana Suara sengau
d. NodulusTidak adaTerkadang ada
e. DeformitasTerjadi diniBiasanya asimetris
Tabel 2.3 Tanda lain yang dapat dipertimbangkan dalam penentuan klasifikasi pada penderita kusta menurut WHO (1982) yang dikutip dalam Depkes RI (2006).2.1.5.2. Klasifikasi Internasional (Madrid 1953): 1. Indeterminate (I) Terdapat kelainan kulit berupa makula berbentuk bulat yang berjumlah 1 atau 2. batas lokasi dipantat, kaki, lengan, punggung pipi. Permukaan halus dan licin.2. Tuberkuloid (T) Terdapat makula atau bercak tipis bulat yang tidak teratur dengan jumlah lesi 1 atau beberapa. Batas lokasi terdapat di pantat,punggung, lengan, kaki, pipi. Permukaan kering, kasar sering dengan penyembuhan di tengah.3. Borderline (B) Kelainan kulit bercak agak menebal yang tidak teratur dan tersebar. Batas lokasi sama dengan Tuberkuloid. 4. Lepromatosa (L) Kelainan kulit berupa bercak-bercak menebal yang difus, bentuk tidak jelas. Berbentuk bintil-bintil (nodule), makula-makula tipis yang difus di badan, merata di seluruh badan, besar dan kecil bersambung simetrik. 2.1.5.3. Klasifikasi Ridley-Jopling (1962) yang di kemukakan oleh Halim et al (2000).1. Tipe Tuberkuloid tuberkuloid (TT) Lesi berupa bercak makuloanestetik dan hipopigmentasi yang terdapat di semua tempat terutama pada wajah dan lengan, kecuali: ketiak, kulit kepala (scalp), perineum dan selangkangan. Batas lesi jelas berbeda dengan warna kulit disekitarnya. Hipopigmentasi merupakan gejala yang menonjol. Lesi dapat mengalami penyembuhan spontan atau dengan pengobatan selama tiga tahun.
2. Tipe Borderline Tuberkuloid (BT) Gejala pada lepra tipe BT sama dengan tipe TT, tetapi lesi lebih kecil, tidak disertai adanya kerontokan rambut, dan perubahan saraf hanya terjadi pembengkakan.3. Tipe Mid Borderline (BB) Pada pemeriksaan bakteriologis ditemukan beberapa hasil, dan tes lepromin memberikan hasil negatif. Lesi kulit berbentuk tidak teratur, terdapat satelit yang mengelilingi lesi, dan distribusi lesi asimetris. Bagian tepi dari lesi tidak dapat dibedakan dengan jelas terhadap daerah sekitarnya. Gejala-gejala ini disertai adanya adenopathi regional.4. Tipe Borderline Lepromatous (BL) Lesi pada tipe ini berupa macula dan nodul papula yang cenderung asimetris. Kelainan syaraf timbul pada stadium lanjut. Tidak terdapat gambaran seperti yang terjadi pada tipe lepromatous yaitu tidak disertai madarosis, keratitis, uslserasi maupun facies leonine.5. Tipe Lepromatosa (LL) Lesi menyebar simetris, mengkilap berwarna keabu-abuan. Tidak ada perubahan pada produksi kelenjar keringat, hanya sedikit perubahan sensasi. Pada fase lanjut terjadi madarosis (rontok) dan wajah seperti singa, muka berbenjol-benjol (facies leonine).2.1.5.4. Klasifikasi WHO (1981) dan modifikasi WHO (1998)1. Pausibasilair (PB)Tipe ini termasuk tipe TT dan BT menurut kriteria Ridley dan Jopling dengan BTA negatif.
2. Multibasilair (MB)Tipe ini termasuk tipe BB, BL, serta LL menurut criteria Ridley dan jopling atau B dan L menurut Madrid serta semua tipe kusta dengan BTA positif (Amiruddin et al 2000).2.1.6. Cacat KustaSebagian besar masalah kecacatan pada penderita ini terjadi akibat penyakit kusta yang terutama menyerang saraf perifer. Menurut Srinivisan (1991) yang dikutip Mukhlasin (2011), saraf perifer yang terkena akan mengalami beberapa tingkat kerusakan, yaitu1. Stage of InvolvementPada tingkat ini saraf menjadi lebih tebal dari normal (penebalan saraf) dan mungkin disertai rasa nyeri spontan pada saraf perifer tersebut, tetapi belum disertai gangguan fungsi saraf, misalnya anastesi atau kelemahan otot.2. Stage of DamagePada tahap ini saraf telah rusak dan fungsi saraf tersebut telah terganggu.Kerusakan fungsi saraf seperti kehilangan fungsi saraf otonom, sensoris dan kelemahan otot menunjukkan bahwa saraf tersebut telah mengenali paralisis lengkap tidak lebih dari 6-9 bulan. Penting sekali untuk mengenali tingkat kerusakan, karena dengan pengobatan pada tingkat ini kerusakan saraf yang permanen dapat dihindari.3. Stage of DestructionPada tingkat ini saraf telah rusak secara lengkap.Diagnosis stage of destruction ditegakkan apabila kerusakan atau paralisis saraf secara lengkap lebih baik dari satu tahun.Pada tingkat ini walaupun dengan pengobatan saraf tidak dapat diperbaiki.WHO (1980) membatasi istilah dalam cacat kusta sebagai berikut:1. ImpairmentSegala kehilangan atau abnormalitas struktur atau fungsi yang bersifat patologik, fisiologik, atau anatomic, misalnya leproma, ginekomastia, madarosis, claw hand, ulkus, dan absorbs jari.2. DissabilitySegala keterbatasan atau kekurang mampuan (akibat impairment) untuk melakukan kegiatan dalam batas kehidupan yang normal bagi manusia.3. Handicap Kemunduran pada seorang individu (akibat impairment atau disability) yang membatasi atau menghalangi penyelesaian tugas normal yang bergantung pada umur, jenis kelamin, dan faktor sosial budaya. Handicap ini merupakan efek penyakit kusta yang berdampak sosial, ekonomi, dan budaya.2.1.6.1. Terjadinya KecacatanTerjadinya cacat tergantung dari fungsi serta saraf mana yang rusak. Diduga kecacatan akibat penyakit kusta dapat terjadi lewat 2 proses (Kemenkes RI 2007), yaitu1. Infiltrasi langsung M. Leprae ke susunan saraf tepi dan organ (misalnya : mata)2. Melalui reaksi kustaSecara umum fungsi saraf dikenal ada 3 macam fungsi saraf, yaitu fungsi motorik memberikan kekuatan pada otot, fungsi sensorik memberi sensasi raba, dan fungsi otonom mengurus kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Kecacatan yang terjadi tergantung pada komponen saraf yang terkena. Apakah sensoris, motoris, otonom, maupun kombinasi dari ketiganya.2.1.6.2. Upaya pencegahan cacatUpaya pencegahan cacat kusta jauh lebih baik dan lebih ekonomis daripada penanggulangannya. Pencegahan ini harus dilakukan sedini mungkin, baik oleh petugas kesehatan maupun oleh penderita itu sendiri dan keluarganya.Disamping itu untuk mengubah pandangan yang salah dari masyarakat antara lain bahwa kusta identik dengan kecacatan. Upaya pencegahan cacat terdiri atas 1. Upaya pencegahan cacat primerKegiatan-kegiatan yang termasuk dalam upaya pencegahan cacat primer adalah sebagai berikut:1) Diagnosis dini2) Pengobatan secara teratur dan adekuat3) Diagnosis dini dan penatalaksanaan neuritis, termasuk silent neuritis4) Diagnosis dini dan penatalaksanaan reaksi (Kemenkes RI 2002).Karena kecacatan kusta adalah akibat gangguan saraf perifer, maka pemeriksaan saraf perifer harus dilakukan secara teliti dan benar, namun cukup sederhana dan murah. Pemeriksaan ini meliputi 1. Pemeriksaan fungsi sensorikUntuk fungsi ini perlu diperiksa fungsi saraf sensorik telapak tangan pada daerah yang disarafi oleh nervus ulnaris dan medianus. Pada daerah telapak kaki adalah untuk daerah yang disarafi oleh nervus Tibialis posterior.2. Pemeriksaan fungsi motorikAlat pengukut yang dipakai adalah MMT (Manual Muscle Testing) dan VMT (Volume Muscle Testing).3. Pemeriksaan fungsi otonomFungsi otonom diperiksa dengan cara memeriksa kebasahan telapak tangan maupun kaki dengan menggenggam tangan penderita (fungsi kelenjar keringat). Pada keadaan dini, bila berbagai gangguan cepat diketahui, maka dengan terapi medikamentosa serta tindakan perlindungan saraf dari kerusakan lebih lanjut, maka hasilnya akan sangat baik (Kemenkes RI 2002).2. Upaya pencegahan cacat sekunderKegiatan yang perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan cacat sekunder, antara lain :1) Perawatan diri sendiri untuk mencegah luka.2) Latihan fisioterapi pada otot yang mengalami kelumpuhan untuk mencegah terjadinya kontraktur.3) Bedah konstruksi untuk koreksi otot yang mengalami kelumpuhan agar tidak mendapat tekanan yang berlebihan4) Bedah septik untuk mengurangi perluasan infeksi sehingga pada proses penyembuhan tidak terlalu banyak jaringan yang hilang5) Perawatan mata, tangan dan kaki yang anestesi atau mengalami kelumpuhan otot (Kemenkes 2002).2.1.7. PengobatanMenurut Dali (2003), tujuan utama program pemberantasan penyakit kusta adalah memutuskan rantai penularan untuk menurunkan insidensi penyakit, mengobati dan menyembuhkan penderita serta mencegah timbulnya cacat. Pasien harus minum obat setiap hari selama 612 bulan tergantung dari klasifikasi penyakit kusta (WHO 1982). Berikut ini adalah beberapa obat anti kusta antara lain,
1. Sulfon1) Dapson (diamino difenil sulfon,DDS)Merupakan dasar pengobatan kusta, bersifat bakteriosttik, namun cara kerjanya belum dapat diketahui. Dosis 100mg bersifat bakterisidal lemah yang merupakan suatu inhibitor kompetitif PABA dan berhubungan dengan metabolism asam folat tetapi sensitivitas M.Leprae yang unik terhadap Dapson menimbulkan perkiraan adanya mekanisme lain yang terlibat. Obat ini aman dan mudah di dapat serta harga terjangkau.Efek samping yang ditimbulkan berupa anemia hemolitik pada pasien G6PD, anemia normositik hipokromik dan lekopenia, sianosis (methemoglobinemia), gangguan gastro intestinal yang rendah dan hepatitis yang ditandai oleh anoreksia dan vomitus, psikotik, albuminurea, erupsi kulit, selain itu Kosasih (2007) menyebutkan efek samping lain dapson adalah nyeri kepala serta neuropati perifer.2) DADDS (diasetil-diamino-difenil-sulfon)Merupakan depot sulfon, penggunaan intramuscular 225 mg dapat aktif sampai lebih dari 2 bulan serta dapat dilakukan dilapangan. Titerplasma yang disuntikkan lebih rendah dari Dapson oral dan terapi yang lama dapat menimbulkan resistensi. Karenanya obat ini tidak boleh digunakan sebagai obat tunggal. Sebagai tambahan untuk terapi oral, diberikan satu injeksi tiap 8-10 minggu. DADDS sering digunakan oleh leprolog Amerika latin, terutama pada penderita yang diragukan kepatuhannya dalam meminum obat. Profilaksis DADDS ini efektif bila disupervisi dengan baik.
3) RifampisinMerupakan derivate semisentik produk fermentasi Streptomyces mediterranei, bekerja melalui inhibisi sintesis RNA, bersifat bakterisidal dan antikusta paling poten dimana menurunkan MI(indeks morfologi) pada kusta lepromatosa menjadi 0 dalam 5 minggu. Rifampisin harus diminum sebelum makan dan tidak boleh diberikan secara tunggal, tidak di rekomendasikan pada kehamilan trisemester pertama, selain itu harga relative mahal menjadi hambatan Negara-Negara berkembang untuk menyediakannnya.Efek samping yang didapat adalah diskolorisasi urin menjadi merah, erupsi kulit terkadang sampai terjadi sindroma Steven-Johnson, pusing, lemah, gangguan gastrointestinal, flushing, hepatitis, tombositopenia, porfiria, kutanea tarda, flu like syndrome, gagal ginjal, nafas pendek, syok, purpura.4) KlofaziminKlofazimin bekerja melalui interaksi DNA mikrobakteria, bersifat bakteriostatik dan bakterisidal lemah, sifat anti kustanya mirip dengan Dapson tetapi sedikit lebih lambat, efektif untuk terapi ENL (Eritema Nodosum Leprosum) dan reaksi reversal, yang tidak dapat diatasi dengan talidomid secara efektif, harus diminum pada waktu makan atau dengan segelas susu, penting dipakai penderita resistensi terhadap dapson, dapat pula digunakan pada penderita ENL menetap yang tidak dapat berhenti minum kortikosteroid dan tidak dapat minum talidomid (wanita hamil dengan ENL).Efek samping terjadi diskolorisasi yang reversible dari ungu sampai coklat kehitaman pada kulit, nyeri abdominal, mual, diare, kematian pernah dilaporkan karena deposit Kristal pada limfatik dengan submukosa gastrointestinal, dimana dosis total klofazimin tinggi, iktiosis atau kekeringan kulit, eksaserbasi pada permulaan terapi, bayi baru lahir kulitnya lebih berpigmentasi saat lampren melewati plasenta selama kehamilan, penderita dengan nyeri abdomen berulang dan diare serta penderita dengan kerusakan hari atau ginjal. 5) Protionamide dan etionamideKeduanya memiliki efek bakterisidal, digunakan apabila klofazimin tidak dapat diberikan, dosis etionamide 250-500 mg/hari, protionamide 250-375 mg/hari. Efek samping yang ditimbulkan hepatitis pada 40% penderita, tetapi protinamid lebih kurng toksik diantara kedua obat tersebut. Intoleransi terhadap obat ini tinggi pada orang Asia, terutama orang-orang Cina. Dapat menyebabkan hepatotoksik, terutama bila dikombinasi dengan rifampisin, WHO Expert Commite on Leprosy merekomendasikan bahwa kedua obat tersebut sebaiknya tidak dipakai sebagai komponen MDT di lapangan, kecuali sangat terpaksa.Pengobatan penderita kusta yang saat ini dilaksanakan di Indonesia adalah dengan menggunakan Multi Drug Therapy (MDT) dengan regimen pengobatan sesuai yang direkomendasikan oleh WHO sebagai berikut :1. Tipe Pausi basilerTabel 2.4. Obat dan Dosis regimen MDTRifampisinDDS
Dewasa600mg/bulan100mg/hari
BB