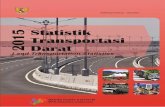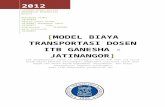Valuasi Ekonomi Moda Transportasi Laut di Indonesia - Studi Kasus Moda Transportasi Gili Matra
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Valuasi Ekonomi Moda Transportasi Laut di Indonesia - Studi Kasus Moda Transportasi Gili Matra
Valuasi Tatanan Ekonomi Moda Transportasi Laut Gendewa Tunas Rancak/4113205004
Institut Teknologi Sepuluh November/Teknik Manajemen Pantai
Sejak dahulu kala trasportasi telah digunakan dalam kehidupan masyarakat. Hanya saja alat
angkut yang digunakan bukan seperti sekarang ini. Sebelum tahun 1800 alat yang
digunakan adalah secara manual atau tenaga manusia, hewan dan sumber tenaga dari
alam. Pengangkutan barang-barang dalam jumlah kecil dan membutuhkan waktu yang
cukup lama.
Antara tahun 1800-1860 transportasi telah mulai berkembang dengan
dimanfaatkannya sumber tenaga mekanis seperti kapal uap, kereta api yang banyak
digunakan dalam dunia perdagangan. Pada tahun 1860-1920 telah ditemukan kendaraan
bermotor, pesawat terbang dalam masa ini angkutan kereta api dan jalan raya memegang
peranan yang sangat penting. Dalam tahun 1920 trasportasi telah mencapai tingkat
peekembangan pada puncaknya (mature) dengan sistem transportasi multi moda (multi moda
sistem).
Transportasi sebagai dasar untuk pembangunan ekonomi ini dan perkembangan
masyarakat serta pertumbuhan industralisasi. Dengan adanya transportasi
menyebabkan adanya sepesialisasi atau pembagian pekerjaan sesuai dengan bidang
keahlian yang dimiliki.
Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau bangsa tergantung pada tersedianya pengangkutan
(transportasi) dalam negara atau bangsa yang bersangkutan. Dalam hal ini dengan
menggunakan transportasi dapat menciptakan suatu barang atau komoditi
yang berguna menurut waktu dan tempat.
I. Kebutuhan Transportasi
1.1 Definisi transportasi
Transportasi memiliki definisi yang sangat beragam, menurut berbagai pakar di bidang
transportasi.Menurut Kamaludin (1987) dalam Romli (2008), Transportasi berasal dari kata
latin transpotare, dimana tran berarti seberang atau sebelah dan portare berarti mengangkut
atau membawa. Jadi tansportasi berarti mengangkut atau membawa (sesuatu) kesebelah lain
atau dari satu tempat ke tempat lainnya.
Menurut Tamin (1997), Transportasi adalah suatu sistem yang terdiri dari prasarana/sarana
dan sistem pelayanan yang memungkinkan adanya pergerakan keseluruh wilayah sehingga
terakomodasi mobilitas penduduk, dimungkinkan adanya pergerakan barang, dan
dimungkinkannya akses kesemua wilayah. Sedangkan fungsi trasportasi menurut Morlok
(1984) adalah untuk menggerakan atau memindahkan orang dan / atau barang dari satu
tempat ke tempat lain dengan menggunakan system tertentu untuk tujuan tertentu. .
Transportasi manusia atau barang biasanya bukanlah merupakan tujuan akhir, oleh karena itu
permintaan akan jasa transportasi dapat disebut sebagai permintaan turunan (derived demand)
yang timbul akibat adanya permintaan akan komoditi atau jasa lainnya. Dengan demikian
permintaan akan transportasi baru akan ada apabila terdapat factor- factor pendorongnya.
Permintaan jasa transportasi tidak berdiri sendiri, melainkan tersembunyi dibalik kepentingan
yang lain. (Morlok, 1984).
Pada intinya, transportasi adalah suatu sistem yang memungkinkan terjadinya pergerakan dan
satu tempat ke tempat lain. Fungsi sistem itu sendiri adalah untuk memindahkan suatu obyek.
Objek yang dipindahkan mencakup benda tak bernyawa seperti sumber daya alam, basil
produksi pabrik, bahan makanan dan benda hidup seperti manusia, serta binatang dan
tanaman. Transportasi dipengaruhi komponen dasar yang berfungsi pada semua sistem
transportasi. Komponen-komponen tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi satu
sama lain. Adapun komponen-komponen tersebut adalah lalu lintas (darat, laut, dan udara),
terminal port (pelabuhan, bandara, stasiun, dan terminal), kendaraan, peti kemas, ruas jalur,
persimpangan dan rencana operasi.
Pada dasarnya permintaan angkutan (transportasi) diakibatkan oleh hal- hal sederhana namun
memiliki dampak yang besar apabila tidak dipenuhi, antara lain:
1. Kebutuhan manusia untuk berpergian dari lokasi lain dengan tujuan mengambil
bagian di dalam suatu kegiatan, misalnya bekerja, berbelanja, kesekolah, dan lain-
lain.
2. Kebutuhan angkutan barang untuk dapat digunakan atau dikonsumsi di lokasi lain.
1.2 Kebutuhan Transportasi bagi Kehidupan
Kebutuhan akan transportasi sangat diperlukan dalam pembangunan suatu negara
ataupun daerah. Dikatakan bahwa transportasi sebagai urat nadi pembangunan kehidupan
politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Bahkan hasil dari banyak
studi menyatakan bahwa transportasi itu merupakan kekuatan pembentuk ekonomi
(transportation is as the formative of economic development and growth) ataupun
perkembangan wilayah. Seringkali pula dikatakan bahwa transportasi lebih merupakan
suatu akibat dari pada suatu sebab. Pernyataan yang sederhana tersebut menunjukan
adanya keterkaitan yang kuat antara “transportasi” dan “pembangunan”.
Kebutuhan transportasi merupakan kebutuhan turunan (derived demand) akibat aktivitas
ekonomi, sosial, dan sebagainya. Dalam kerangka makro-ekonomi, transportasi merupakan
tulang punggung perekonomian nasional, regional, dan lokal, baik di perkotaan maupun di
pedesaan. Harus diingat bahwa sistem transportasi memiliki sifat sistem jaringan di mana
kinerja pelayanan transportasi sangat dipengaruhi oleh integrasi dan keterpaduan jaringan.
Sarana transportasi yang ada di darat, laut, maupun udara memegang peranan vital dalam
aspek sosial ekonomi melalui fungsi distribusi antara daerah satu dengan daerah yang lain.
Distribusi material dan manusia akan menjadi lebih mudah dan cepat bila sarana transportasi
yang ada berfungsi sebagaimana mestinya sehingga transportasi dapat menjadi salah satu
sarana untuk mengintegrasikan berbagai wilayah di Indonesia. Melalui transportasi penduduk
antara wilayah satu dengan wilayah lainya dapat ikut merasakan hasil produksi yang rata
maupun hasil pembangunan yang ada.
Skala ekonomi (economy of scale), lingkup ekonomi (economy of scope), dan keterkaitan
(interconnectedness) harus tetap menjadi pertimbangan dalam pengembangan transportasi
dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah yang kerap didengungkan akhir-akhir ini.
Ada satu kata kunci ini disini, yaitu integrasi, di mana berbagai pelayanan transportasi harus
ditata sedemikian rupa sehingga saling terintegrasi, misalnya truk pengangkut kontainer,
kereta api pengangkut barang, pelabuhan peti kemas, dan angkutan laut peti kemas,
semuanya harus terintegrasi dan memungkinkan sistem transfer yang terus menerus
(seamless).
Kebutuhan angkutan bahan-bahan pokok dan komoditas harus dapat dipenuhi oleh sistem
transportasi yang berupa jaringan jalan, kereta api, serta pelayanan pelabuhan dan bandara
yang efisien. Angkutan udara, darat, dan laut harus saling terintegrasi dalam satu sistem
logistik dan manajemen yang mampu menunjang pembangunan nasional.
Transportasi jika ditilik dari sisi sosial lebih merupakan proses afiliasi budaya dimana ketika
seseorang melakukan transportasi dan berpindah menuju daerah lain maka orang tersebut
akan menemui perbedaan budaya dalam bingkai kemajemukan Indonesia. Disamping itu
sudut pandang sosial juga mendeskripsikan bahwa transportasi dan pola-pola transportasi
yang terbentuk juga merupakan perwujudan dari sifat manusia. Contohnya, pola pergerakan
transportasi penduduk akan terjadi secara massal dan masif ketika mendekati hari raya. Hal
ini menunjukkan perwujudan sifat manusia yang memiliki tendesi untuk kembali ke kampung
halaman setelah lama tinggal di perantauan.
1.3 Moda Transportasi di Indonesia
Moda transportasi merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan alat angkut yang
digunakan untuk berpindah tempat dari satu tempat ketempat lain. Moda yang biasanya
digunakan dalam transportasi dapat dikelompokkan atas moda yang berada di darat, berlayar
di perairan laut dan pedalaman, serta moda di udara. Moda-moda ini pun masih akan dibagi
lagi menjadi beberapa bagian kecil sesuai dengan karakteristik infrastruktur, pengangkutan,
dan spasial.
Indonesia sebagai negara kepulauan yang tersebar denga 17.500 pulau hanya bisa
terhubungkan dengan baik dengan sistem transportasi multi moda, tidak ada satu modapun
yang bisa berdiri sendiri. Masing-masing moda mempunyai keunggulan dibidangnya masing-
masing. Pemerintah berfungsi untuk mengembangkan keseluruh moda tersebut dalam rangka
menciptakan sistem transportasi yang efisien, efektif dan dapat digunakan secara aman dapat
menempuh perjalanan dengan cepat dan lancar.
Jaringan transportasi dapat dibentuk oleh moda transportasi yang terlibat yang salaing
berhubungan yang rangkai dalam Sistem Transportasi Nasional (Sistranas). Masing-masing
moda transportasi memiliki karakteristik teknis yang berbeda dan pemanfaatannya
disesuaikan dengan kondisi geografis daerah layanan (wikibooks, 2012).
Sistem Transportasi Nasional (Sistranas) adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara
kesisteman terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai, danau,
dan penyeberangan, transportasi laut serta transportasi pipa, yang masing-masing terdiri dari
sarana dan prasarana, kecuali pipa, yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat
lunak dan perangkat pikir membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif
dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang, yang terus berkembang
secara dinamis (wikibooks, 2012)
Moda Transportasi Darat
1. Jalan
Merupakan moda yang paling banyak digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk
memenuhi kebutuhan transportasi. Moda jalan mempunyai fleksibilitas yang tinggi
sepanjang didukung dengan jaringan infrastruktur. Infrastruktur sendiri dibatasi oleh
geografis jalan yang dilalui pegunungan, perairan yang sulit dilalui oleh jalan, walaupun
jembatan atau terowongan yang menghubungkan dua pulau dapat dibangun, tetapi hal ini
masih terkendala dengan jarak yang harus dilalui atau pun kelayakan teknis atau pun
ekonomis.
Sistem transportasi jalan membutuhkan biaya operasi dan perawatan yang tinggi baik
untuk alat angkutnya maupun biaya perawatan prasarana sehingga hanya sesuai untuk
jarak perjalanan pendek dan menengah saja. Walaupun kalau kita melihat kepada
angkutan barang di Indonesia seperti antara pulau Jawa dengan pulau Sumatera masih
didominasi oleh angkutan jalan.
2. Kereta api
Merupakan moda yang digunakan pada koridor dengan jumlah permintaan yang tinggi,
dimana alat angkut kereta api yang berjalan diatas media khusus (rel). Tingkat
fleksibilitas moda kereta api tidak seperti moda jalan, karena hanya dapat digunakan bila
didukung oleh jaringan infrastruktur rel kereta api, dimana tidak seluruh Provinsi di
Indonesia memiliki infrastruktur rek kereta api.
Sistem transportasi kereta api
dapat dioperasikan dengan biaya
operasi dan biaya perawatan yang
lebih rendah dari moda jalan,
namun biaya investasi awalnya
sangat tinggi sehingga hanya
sesuai digunakan untuk angkutan
penumpang yang bersifat massal
baik di perkotaan maupun antar
kota, serta angkutan barang.
Angkutan barang yang
menggunakan kereta api biasanya
dalam bentuk angkutan peti kemas
pada kereta flat bed atau pun
untuk mengangkat komoditi curah
baik cair maupun padat.
3. Angkutan Pipa
Merupakan moda yang umumnya
digunakan untuk mendistribusikan bahan
berbentuk cair atau pun gas. Pipa disusun
diatas tanah, ditanam pada kedalaman
tertentu di tanah atau pun digelar melalui
dasar laut. Biaya operasi dan biaya
perawatan rendah, lebih rendah dari biaya
moda jalan dan moda kereta api, nam un
biaya investasi infrastrukturnya sangat
tinggi. Angkutan pipa efisien digunakan
untuk mengangkut cairan atau gas dalam
jumlah barang yang diangkut tinggi pada
jaringan primer.
Didaerah perkotaan jaringan pipa jarak pendek digunakan untuk mengalirkan berbagai
keperluan diantaranya sistem drainase kota untuk mengelola pembuangan air hujan dan
pengendalian banjir, sistem pembuangan air kotor, sistem air bersih yang biasanya
dikelola oleh Perusahaan Air Minum/PAM, Gas Kota yang digunakan untuk kebutuhan
energi untuk masak atau pemanasan
Moda Transportasi Pelayaran
Karena sifat fisik air yang menyangkut daya apung dan gesekan yang terbatas, maka
pelayaran merupakan moda angkutan yang paling efektif untuk angkutan barang jarak jauh
barang dalam jumlah yang besar. Pelayaran dapat berupa pelayaran paniai, pelayaran antar
pulau, pelayaran samudra ataupun pelayaran pedalaman melalui sungai atau pelayaran di
danau. Didalam pelayaran biaya terminal dan
perawatan alur merupakan komponen biaya
paling tinggi, sedangkan biaya pelayarannya
rendah. Ukuran kapal cenderung semakin besar
pada koridor-koridor pelayaran utama, dimana
pada tahun 1960an ukuran kapal yang paling
besar mencapai 100.000 dwt tetapi sekarang
sudah mulai digunakan kapal tangker MV
Knock Nevis 650 ribu ton dengan panjang 458
meter, draft 24,6 meter (Explorepedia, 2011)
Moda Transportasi Udara
Moda transportasi udara mempunyai
karakteristik kecepatan yang tinggi dan
dapat melakukan penetrasi sampai
keseluruh wilayah yang tidak bisa dijangkau
oleh moda transportasi lain. Di Papua ada
beberapa kota yang berada di pedalaman
yang hanya dapat dihubungkan dengan
angkutan udara, sehingga papua merupakan
pulau dengan lebih dari 400 buah
bandara/landasan pesawat/air strip dengan
panjang landasan antara 800 sampai 900
meter. Perkembangan industri angkutan udara nasional, Indonesia sangat dipengaruhi oleh
kondisi geografis wilayah yang ada sebagai suatu negara kepulauan. Oleh karena itu,
Angkutan udara mempunyai peranan penting dalam memperkokoh kehidupan berpolitik,
pengembangan ekonomi, sosial budaya dan keamanan & pertahanan (Wikibook, 2012)
Kegiatan transportasi udara terdiri atas: angkutan udara niaga yaitu angkutan udara untuk
umum dengan kompensasi biaya transport penumpang, dan angkutan udara bukan niaga yaitu
kegiatan angkutan udara untuk memenuhi kebutuhan sendiri dengan kegiatan utama bukan di
bidang angkutan udara. Sebagai tulang punggung transportasi adalah angkutan udara niaga
berjadwal, sebagai penunjang adalah angkutan niaga tidak berjadwal, sedang pelengkap
adalah angkutan udara bukan niaga.
1.4 Transportasi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Transportasi sebagai Kebutuhan Dasar dan Prasyarat Pembangunan Ekonomi
Pada awalnya infrastrukur seperti transportasi berperan dalam memenuhi kebutuhan dasar
manusia. Berbagai aktifitas terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar memerlukan
ketersediaan infrastruktur yang baik, sekarang transportasi berperan penting dalam
mengoakomodasi aktifitas social dan ekonomi masyarakat. Peran lain pada tahap ini adalah
sebagai fasilitas bagi system produksi dan investasi sehingga memberikan dampak positif
pada kondisi ekonomi baik pada tingkat nasional maupun daerah.
Disisi lain, pembangunan sarana dan prasarana transportasi dapat membuka aksesibilitas
sehingga meningkatkan produksi masyarakat yang berujung pada peningkatan daya beli
masyarakat.
Penanggulangan kemiskinan membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang cukup, dengan
mengupayakan kombinasi yang optimum antara pertumbuhan ekonomi dengan upah
minimum pekerja. Penanggulangan kemiskinan memerlukan penguatan koordinasi dalam
pelaksanaan program-programnya yang didesain melalui partisipasi aktif masyarakat serta
pembedayaan langsung.
Transportasi dan Daya Saing
Daya saing merupakan salah satu elemen penting dalam penentuan posisi Indonesia dalam
kerangka perdagangan global. Dalam bidang ekonomi, upaya peningkatan daya saing dalam
jangka pendek dapat dilakukan dengan memacu pemanfaatan kapasitas industri yang
menganggur melalui pengurangan hambatan perdagangan dalam dan luar negeri,
meningkatkan pembiayaan perdagangan, serta mempromosikan dan mengembangkan produk
ekspor dan pariwisata.
Dalam jangka menengah akan dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan daya saing,
antara lain dengan terus memperkuat institusi pasar serta mengmbangkan industri
berkeunggulan kompetitif berlandaskan keunggulan komparatif didukung oleh kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi.
Transportasi dan Otonomi Daerah
Dalam era Otonomi daerah saat ini, transportasi memegang peranan penting bagi kelancaran
pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Perubahan sistem dari sentralisasi menjadi
desentralisasi membawa angin segar bagi daerah agar sebisa mungkin dapat mendayagunakan
kemampuan dan potensi daerahnya untuk kelangsungan pembangunan. Distribusi barang dan
jasa yang baik dan lancar menuntut keberadaan sarana dan prasarana transportasi yang
memadai agar distribusi mampu mengcover seluruh lingkup daerah tersebut.
Sebagai contoh adalah Propinsi Papua. Semenjak pemberlakuan otonomi daerah, propinsi
Papua dituntut untuk lebih mandiri dalam pembangunan daerahnya dan pembangunan daerah
Papua akan berjalan lancar jika distribusi barang, jasa, maupun manusia (dalam hal ini adalah
tenaga ahli) berjalan sebagaimana mestinya. Namun demikian perbedaan spasial yang ada
antara kota-kota besar di Papua dan daerah pedalaman memberikan hambatan yang cukup
besar dalam distribusi.
Perbedaan spasial disamping menyajikan keberagaman sumber daya antar daerah juga
memberikan hambatan spasial yang tidak ringan baik itu dikarenakan oleh perbedaan
topografi, perbedaan kultur, dan sebagainya. Selama ini distribusi barang dan jasa yang
mampu mengcover seluruh wilayah Papua cukup mengandalkan sarana transportasi udara
berupa penerbangan perintis. Melalui penerbangan perintis, kebutuhan akan distribusi barang
dan jasa dapat tercover, mengingat hambatan spasial yang tidak dapat diatasi oleh sarana
transportasi darat. Namun, selama ini titik pusat penerbangan perintis di Papua hanya terdapat
di kota-kota besar seperti Jayapura, Merauke, Manokwari, Sorong, dan Biak. Disamping itu
armada penerbangan perintis yang terdapat di Papua masih belum memadai dalam
mengcover seluruh distribusi barang agar lebih cepat dan memiliki kuantitas yang besar. Hal
ini disebabkan pesawat transport yang selama ini melayani rute penerbangan perintis tersebut
masih berupa pesawat berbaling-baling berbadan kecil disamping kondisi bandara yang
belum mampu didarati pesawat sekelas Boeing 737. Sehingga sampai saat ini pembangunan
di Papua belum berjalan secara optimal.
Era otonomi daerah juga memberikan kesempatan bagi tiap-tiap daerah untuk memekarkan
diri. Hal tersebut menyebabkan banyak wilayah mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan,
Kelurahan, sampai Desa yang ingin melepaskan diri dari struktur yang lama karena merasa
mampu mandiri untuk berdiri sebagai Propinsi, Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan sampai
dengan Desa yang baru. Salah satu contoh propinsi baru hasil pemekaran daerah adalah
propinsi Bangka-Belitung. Propinsi baru penghasil timah ini memiliki modal yang lebih dari
cukup untuk berdiri sebagai propinsi. Namun demikian hambatan spasial berupa kondisi fisik
propinsi tersebut yang berupa kepulauan dengan dua pulau terbesar yaitu pulau Bangka dan
Belitung cukup memberikan permasalahan bagi distribusi pembangunan. Pengadaan dan
optimalisasi armada transportasi baik armada laut maupun udara akan memudahkan distribusi
barang dan jasa bagi propinsi baru tersebut. Dengan mengandalkan sarana transportasi laut
yang memiliki jumlah armada yang belum memadai, nampaknya Propinsi Bangka-Belitung
patut memikirkan optimalisasi sarana transportasi yang ada maupun memikirkan jalur
transportasi udara agar mampu melancarkan distribusi pembangunan.
Dari contoh diatas dapat disimpulkan bahwa transportasi memegang peranan vital bagi
pembangunan ekonomi daerah. Melalui tersedianya sarana dan prasarana yang baik maka
distribusi barang, jasa, maupun manusia akan mampu berjalan lebih lancar, cepat, dan dalam
kuantitas yang besar sehingga pembangunan di daerah akan berjalan dengan baik.
Dengan karakteristik Negara kepulauan, moda transportasi yang dapat menjadi tulang
punggung pembangunan, pertumbuhan ekonomi, serta pemerataan pembangunan adalah
transportasi laut. Dengan catatan, tidak mengesampingkan moda transportasi lainnya, dan
pelibatan multistakeholder untuk pembangunan berkelanjutan melalui sector transportasi,
dalam hal ini adalah transportasi laut
II. Transportasi Laut
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki wilayah seluas 7,7 juta
Km2, dengan luas lautan
2/3 wilayah Indonesia, dan garis pantai terpanjang ke empat di dunia
sepanjang 95.181 km, serta memiliki 17.500 pulau mempunyai potensi ekonomi pada jasa
transportasi laut (pelayaran) yang sangat besar, karena sudah tidak dapat dielakkan lagi
bahwa transportasi laut (kapal) merupakan sarana transportasi utama guna menjangkau dan
menghubungkan pulau-pulau di wilayah nusantara sehingga menciptakan konektifitas antar
pulau di Indonesia
Salah satu strategi percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional (MP3EI) adalah
dengan mengedepankan penguatan konektifitas antar pulau terutama pulau-pulau terluar.
Konektifitas ini hanya bisa terwujud apabila transportasi laut di negara kepulauan terus
diperankan secara signifikan.
2.1 Sistem Transportasi Laut
Jaringan transportasi laut sebagai salah satu bagian dari jaringan moda transportasi air
mempunyai perbedaan karakteristik dibandingkan moda transportasi lain yaitu mampu
mengangkut penumpang dan barang dalam jumlah besar dan jarak jauh antar pulau dan antar
negara.
Jaringan Prasarana
Jaringan prasarana transportasi laut terdiri dari simpul yang berwujud pelabuhan laut dan
ruang lalu lintas yang berwujud alur pelayaran. Pelabuhan laut dibedakan berdasarkan peran,
fungsi dan klarifikasi serta jenis. Berdasarkan jenisnya pelabuhan dibedakan atas:
1. Pelabuhan umum digunakan untuk melayani kepentingan umum sesuai ketetapan
pemerintah dan mempunyai fasilitas karantina, imigrasi dan bea cukai.
2. Pelabuhan khusus yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri guna menunjang
kegiatan tertentu.
Berdasarkan Peran dan Fungsi pelabuhan laut, pelabuhan dapat dibagi menjadi:
1. Pelabuhan internasional hub (utama primer) adalah pelabuhan utama yang memiliki peran
dan fungsi melayani kegiatan bongkar muat penumpang dan barang internasional dalam
volume besar karena kedekatan dengan pasar dan jalur pelayaran internasional serta
berdekatan dengan jalur laut kepulauan Indonesia.
2. Pelabuhan lnternasional (utama sekunder) adalah pelabuhan utama yang memiliki peran
dan fungsi melayani kegiatan bongkar muat penumpang dan barang nasional dalam
volume yang relatif besar karena kedekatan dengan jalur pelayaran nasional dan
internasional serta mempunyai jarak tertentu dengan pelabuhan internasional lainya.
3. Pelabuhan nasional (utama tersier) adalah pelabuhan utama memiliki peran dan fungsi
melayani kegiatan bongkar muat penumpang dan barang nasional dengan volume sedang
dengan memperhatikan kebijakan pemerintah dalam pemerataan pembangunan nasional
dan meningkatkan pertumbuhan wilayah, mempunyai jarak tertentu dengan jalur/rute
lintas pelayaran nasional dan antar pulau serta berada (dekat) dengan pusat pertumbuhan
wilayah ibukota kabupaten/kota dan kawasan pertumbuhan nasional.
4. Pelabuhan regional adalah pelabuhan pengumpan yang berfungsi untuk melayani kegiatan
bongkar muat penumpang dan barang dalam jumlah kecil dan jangkauan pelayanan antar
kabupaten/kota serta merupakan pengumpan kepada pelabuhan utama.
5. Pelabuhan lokal adalah pelabuhan pengumpan yang berfungsi khususnya untuk melayani
kegiatan bongkar muat penumpang dan barang dalam jumlah kecil dan jangkau
pelayanannya antar kecamatan dalam kabupaten/kota serta merupakan pengumpan kepada
pelabuhan utama dan pelabuhan regional.
Berdasarkan peran dan fungsi pelabuhan khusus yang bersifat nasional/internasional yang
melayani kegiatan bongkar muat barang berbahaya dan beracun (B3) dengan lingkup
pelayanan yang bersifat lintas provinsi dan internasional. Penyelenggaraan pelabuhan umum
dapat dibedakan atas pelabuhan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau
dapat dilimpahkan pada BUMN, dan pelabuhan umum yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota atau dapat dilimpahkan pada BUMD.
Ruang lalu lintas laut (seaways) adalah bagian dari ruang perairan yang ditetapkan untuk
menampung kapal lautyang berlayar atau berolah gerak pada satu lokasi/pelabuhan lainnya
melalui arah dan posisi tertentu. Alur pelayaran adalah bagian dari ruang lalu lintas laut yang
alami maupun buatan yang dari segi kedalaman, lebar dan hambatan pelayaranlainnya
dianggap layak untuk dilayari. Alur pelayaran dicantumkan dalam peta laut dan buku
petunjuk pelayaran serta diumumkan oleh instansi yang berwenang
Alur pelayaran terdiri dari: (1) alur pelayaran internasional yaitu alur laut kepulauan untuk
perlintasan yang sifatnya terus menerus, langsung dan cepat bagi kapal asing yang melalui
perairan Indonesia (innoncent passages), seperti Selat Lombok-Selat Makassar, Selat Sunda-
Selat Karimata, Laut Sawu-Laut Banda-Laut Maluku, Laut Timor-Laut Banda-Laut Maluku,
yang ditetapkan dengan memperhatikan factor-faktor pertahanan keamanan,keselamatan
berlayar, rute yang biasanya digunakan untuk pelayaran internasional, tata ruang kelautan,
konservasi sumber daya alam dan lingkungan, dan jaringan kabel/pipa dasar laut serta
rekomendasi organisasi internasional yang berwenang, dan (2) alur pelayranan nasional
meliputi alur pelayaran yang menghubungkan pelabuhan nasional dengan pelabuhan
internasional atau pelabuhan internasional hub, alur yang menghubungkan atar pelabuhan
nasional, alur pelayaran yang menghubungkan antara pelabuhan nasional dan pelabuhan
regional, serta alur pelayran antara pelabuhan regional
Alur Laut Kepulauan Indonesia (dilewati Kapal Laut dan Pesawat Udara)
Jaringan Pelayanan
Jaringan pelayanan transportasi laut dibedakan menurut kegiatan dan sifat
pelayanannya.Berdasarkan kegiatannya,jaringan transportasi laut terdiri dari:
1. Jaringan transportasi laut dalam negeri, yang terdiri dari:
a. Jaringan transportasi laut utama yang menghubungkan antar pelabuhan yang
berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi
b. Jaringan transportasi laut pengumpan yaitu yang menghubungkan pelabuhan yang
berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi dengan pelabuhan yang bukan
berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi. Disamping itu, jaringan ini juga
menghubungkan pelabuhan-pelabuhan yang berfungsi sebagai pusat akumulasi dan
distribusi
c. Jaringan transportasi laut perintis yaitu menghubungkan daerah terpencil atau daerah
yang belum berkembang dengan pelabuhan yang berfungsi sebagai pusat akumulasi
dan distribusi atau pelabuhan yang bukan berfungsi sebagai pusat akumulasi dan
distribusi.
2. Jaringan transportasi laut luar negeri
Jaringan transportasi laut luar negeri ditetapkan dengan memperhatikan perkembangan pusat
industri, perdagangan dan pariwisata pengembangan daerah, keterpaduan intra dan antar
moda transportasi dan perwujudan kesatuan Wawasan Nusantara. Berdasarkan sifat
pelayanannya jaringan pelayanan transportasi laut terdiri atas:
a. Jaringan pelayanan transportasi laut tetap dan teratur yaitu jaringan pelayanan
dengan rute dan jadwal yang telah ditetapkan;
b. Jaringan pelayanan transportasi laut tidak tetap dan tidak teratur yaitu jaringan
pelayanan dengan rute dan jadwal yang tidak ditetapkan.
2.2 Pelabuhan
Menurut PP RI No 69 Tahun 2001 tentang kepelabuhanan, yang dimaksud ddengan
pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-
batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi dipergunakan
sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik-turun penumpang dan/atau bongkar muat
barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan keigatan penunjang
pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
Penyelenggara pelabuhan antara lain unit pelaksana teknis/satuan kerja dan Badan Usaha
Pelabuhan. Unit pelakasana teknis/satuan kerja adalah unit organisasi pemerintah,
pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Sedangan Badan Usaha Pelabuhan
(BUP) adalah badan usaha milik Negara atau badan usaha miliki daerah yan gkhusus
didirikan untuk mengusahakan jasa kepelabuhanann di pelabuhan umum.
Jenis Pelabuhan
Jenis Pelabuhan dapat dibagi menurut:
1. Alamnya
Menurut alamnya pelabuhan laut dapat dibagi menjadi pealbuhan terbuka dan pelabuhan
tertutup. Pelabuhan terbuka adalah pelabuhan dimana kapal-kapal bisa masuk dan
merapat secara langsun tanpa bantuan pintu-pintu air. Pelabuhan di Inonesia pada
umumny merupakan pelabuhan terbuka. Pelabuhan tertutup adalah pelabuhan dimana
kapal-kapal yang masuk harus melalui beberapa pintu air. Pelabuhan tertututp dibuat
pada pantai dimana terdapat perbedaan pasang surut yang besar dan waktu pasang
surutnya berdekatan. Pelabuhan ini tidak terdapat di Indonesia, namun dapat dijumpai di
Liverpool dan Terusan Panama (Suyono, 2003)
2. Pelayanannya
Berdasarkan PP 69/2001, pelabuhan menurut sarana pelayanannya dapat dibagi menjadi
pelabuhan umum dan pelabuhan khusus. Pelabuhan umum adalah pelabuhan yang
diselenggarakan untuk kepentinan masyarakat umum. Pelaksanan pelabuhan umum
adalah BUP atau unit pelaksana teknis/satuan kerja pelabuhan. Pelabuhan khusus adalah
pelabuahan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menungkang keiatan tertentu.
Pengelola pelabuhan khusus adalah Pemerintah, Pemerintha Provinsi, Pemerintah
Kabupaten, Kota atau Badan Hukum Indonesia yan memiliki izin.
3. Lingkup Pelayaran yang dilayani
Berdaasarkan PP No 69/2001, pasal 5 dan 6, peran dan fungsi pelabuhan dibagi menjadi:
a. Pelabuhan internasional hub adalah pelabuhan utama primer yang berfungsi
melayani kegiatan dan alih muatan angkutan laut nasional dan internasional dalam
jumlah bersar dan jangkauan pelayaran yang sanagat luas serta merupakan simpul
dalam jaraingan transportasi lait internasional
b. Pelabuhan internasional adalah pelabuhan untama sekunder yang erfdunsi melayani
kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah besar
dan jangakaun pelayanann yan luas sea merupakan simpul dalam jaringan
transportasi laut internasional.
c. Pelabuhan Nasioanal adalah pelabuhan utama tersier yang berfungsi sebagai
melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dan internasional dalam
jumlah menengah serta merupakan simpul dalam jaringan transportasi tingkat
provinsi.
d. Pelabuhan regional adalah pelabuhan pengumpan primer yang berfungsi melayani
kegiatan dan alih muatan angkutan laut nasional dalam jumlah yang relative kecil
serta merupakan pengumpan dari pelabuahan utama.
e. Pelabuhan Lokal adalah pelabuhan pengumpan sekunder yang berfunsi melayani
kegiatan ankutan laut regional dalam jumlah kecil serta merupakan pengumpan pada
pelabuhan utama dan/atau pelabuhan regional.
4. Kegiatan Perdagangan Luar Negeri
Menurut kegiatan perdagangan kuar negeri yang dilayani, jenis pelabuhan bisa dibagi
menadi pelabuhan impor dan pelabuhan ekspor. Pelabuan impor adalah pelabuhan yan
melayani masuknya barang-barang dari luar negeri. Pelabuhan ekspor adalah pelabuhan
yan meklayani penjualan barag-barang ke luar negeri (Suyono, 2003).
5. Kapal Yang Dipebolehkan Singgahmenurut kapal yang diperbolehka singgah,
berdasarkan Indische Scheepvart-Wet (Staatablad 1936 No. 700) jenis pelabuhan dibagiu
menjadi pelabuha laut dan pelabuhan pantai. Pelabuhan laut adalah pelabuhan yang
terbuka bagi perdagangan luar negeri dan dapat disinggahi oleh kapal-kapal dari Negara
tetangga. Sedangkan pelabuhan pantai adalah pelabuhan yang tidak terbuka untuk
perdagangan dengan luar negeri dan hanya dapat diergunakan oleh kapal-kapal dari
Indonesia
6. Wilayah pengawasan Bea-Cukai
Dari segi pembagian wilayah bea-cukai, jenis pelabuhan dibagi menjadi custom port dan
free port. Custom port adalaha pelabuhan yan berada di bawah pengawasan Bea-cukai.
Sedangkan free port merupakan pelabuahn yang berada di luar penggawasan Bea-Cukai
(Suyono, 2003).
7. Kegiatan Pelayarannya
Dilihat dari segi pelayrannya, pelabuhan dibagi menjadi tigga jenis , yaitu pelabuhan
samudera, pelabuhan nusantara (pelabuhan interinsuler), dan pelabuhan pelayaran rakyat.
Contoh pelabuhan samudera adalah pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta dan Tanjung
Perak di Surabaya. Contoh pelabuhan nusantara adalah pelabuhan Banjarmasin di
Kalimantan Sleatan, sedangkan pelabuhan pelayaran rakyat adalah pelabuhan Sunda
Kelapa di Pasar Ikan, Jakarta (Suyono, 2003)
8. Perannya dalam Pelayaran
Menurut perannya dalam pelayaran, pelabuhan dibagi meenjadi dua jenis, yaitu
pelabuhan transito dan pelabuhan ferry. Pelabuhan transito adalah pelabuhan yang
mengerjakan transshipment cargo. Contohnya adalah pelabuhan singapura. Pelabuhan
ferry adalah pelabuhan penyebrangan. Pelayanan dilakukan oleh kapal ferry yang
menghubungkan dua tempat dengan sistem roll on dan roll off dengan mebawa
penumpan dan kendaraan. Contoh pelabuhan ferry adalah pelabuhan Banyuwangi-
Gilimanuk atau merak-Bakauheni (Suyono, 2003)
Fungsi Pelabuhan
Secara umum, menurut Suyono (2013) pelabuhan memiliki 4 fungsi utama, yaitu sebagai
tempat pertemuan dan (interface), gapura (gateway), entitas industry dan perdagangan, dan
mata rantai transportasi.
1. Tempat pertemuan
Pelabuhan merupakan tempat pertemuan dua moda transportasi utama, yaitu darat dan
laut serta berbagai kepentingan yang saing terkait. Baran-barang yang diangku dengan
kapal laut akan dibongkat dan dipindahkan ke angkutan darat seperti truk atau kereta api.
Sebaliknya, barang-barang yang diangkut menggunakan truk atau kereta api, di
pelabuhan akan dibongkar dan dimuat ke kapal. Oleh karena di pelabuhan berbagai
kepentinan bertemu, maka di pelabuhan akan berdiri bank yang melayani pelayaran
maupun kegiatan ekspor impor. Pelabuhan merupakan tempat bagi instansi Bea-Cukai
memungut bea masuk. Selain itu, syahbandar akan memeriksa keselamatan pelayaran.
Selain itu, dipeabuhan banyak berdiri perusahaan yang melayani pelayaran, seperti
leveransir, pemasok peralatan kapal, dan sebagainya.
2. Gapura
Pelabuhan berfungsi sebagai gapura atau pintu gerbag suatu Negara. Warga Negara dan
barang-barang dari Negara asing yang memiliki pertalian ekonomi masuk ke suatu
Negara akan melewati pelabuhan tersebut. Sebaai pintu gerbang Negara,, citra Negara
sangat ditentukan oleh baiknya pelayanan, kelancaran serta kebersihan di pelabuhan
tersebut. Pelayanan dan kebersihan di pelabuhan merupakan cermin dari Negara yan
bersangkutan.
Beberapa pelabuhan di luar begeri, ketika kapal bersandar akan segera dikunjungi ileh
petugas pariwisata dari neara setempat. Petugas tersebut akan membagikan brosur-brosur
mengenai tempat oariwisata yang dekat dengan pelabuhan serta informasi tempat-tempat
berbelanja atau kuliner. Selain itu, ada juga brosue yang memberikan informasi
mengenai jumlah penduduk, adat istiadat, serta sarana transportasi yang tersedia.
3. Entitas industry
Denan berkembangnya industry berorientasi ekspor maka fungsi pelabuhna menjadi
sanga pentin. Dengan adanya pelabuhan, hal itu akan memudahka industry mengirim
produknya dan mendatangkan bahan baku. Dengan demikian, pelabuhan berkembang
menjadi suatu jenis industry sendiri yang menjadi ajang bisnis berbaai jeis usaha, mulai
dari transportasi, perbankan, perusahaan leasing peralatan dan sebagainya.
4. Mata rantai transportasi
Pelabuhan merupakan baian dari rantai transpiortasi, di pelabuhan berbagai moda
transportasi bertemu dan bekerja. Pelabuhan laut merupakan salah satu titik dari mata
rantai angkutan darata dengan ankutan laut. Oran dan barang yang diankut dengan kereta
api bisa diangkut mengikuti rantai transportasi dengan menggunakan kapal laut. Oleh
karena itu, akses jalan mobil, rel kereta api, jalur dari dank e badnara sangatlah penting
bagi suatu pelabuhan. Selain itu sarang pendukung, seperti perahu kecil dan tongkang
akan sangat membantu kelancaran aktivitas pelabuhan sebagai salah satu mata rantai
transportasi.
3.1 Jalur Transportasi Laut di Indonesia
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan ditinjau dari segi daya saing, pangsa pasar
angkutan laut baik antar pulau maupun antar negara masih dikuasai oleh armada niaga
berbendera asing. Kemampuan daya angkut armada nasional untuk muatan dalam negeri baru
mencapai 54,5 persen dan hanya 4 persen untuk ekspor, selebihnya masih dikuasai oleh
armada asing. Persoalan bagi Indonesia tidak sekedar bagaimana mengembangkan angkutan
laut yang kompetitif, tetapi juga bagaimana mengembangkan pelabuhan Indonesia agar dapat
memenuhi standar internasional. Indonesia belum memiliki pelabuhan yang memenuhi
standar internasional dan hingga kini, semua pelabuhan Indonesia masih berstatus feeder
port, dan belum berstaturs hub port. Sekitar 70 % dari ekspor barang dan komoditas
Indonesia harus melalui Singapura. Dalam meningkatkan pembangunan pelayaran nasional,
dibutuhkan sasaran yang jelas. Sasaran tersebut mencakup lima hal, pertama, harus dapat
memenuhi asas cabotage sebesar 100% dan 40% export import share untuk kapal Indonesia
(Antaranews, 2012).
Kedua, perlu dibangunnya sebagian besar kapal di Indonesia sehingga menjadikan Indonesia
sebagai pusat pelayaran kapal dunia. Ketiga, pelayaran rakyat harus berperan penting dalam
standar logistik nasional. Keempat, pelayaran harus memiliki sistem dan manajemen
pelabuhan berstandar internasional, dan yang terakhir dibutuhkan pembangunan pusat
pendidikan dan pelatihan serta penyelia Sumber Daya Masyarakat (SDM) di bidang
pelayaran dan perkapalan yang terkemuka. Melalui sasaran tersebut lanjutnya, diharapkan
para pemangku kepentingan pelayaran dapat segera mengambil tindakan untuk
merencanakan langkah-langkah beyond cabotage sehingga para pelaku pelayaran Indonesia
mampu bersaing di kancah global.
Ketiga, pelayaran rakyat harus berperan penting dalam standar logistik nasional. Keempat,
pelayaran harus memiliki sistem dan manajemen pelabuhan berstandar internasional, dan
yang terakhir dibutuhkan pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan serta penyelia
Sumber Daya Masyarakat (SDM) di bidang pelayaran dan perkapalan yang terkemuka.
Melalui sasaran tersebut lanjutnya, diharapkan para pemangku kepentingan pelayaran dapat
segera mengambil tindakan untuk merencanakan langkah-langkah beyond cabotage sehingga
para pelaku pelayaran Indonesia mampu bersaing di ranah global.
Apabila sektor pelayaran dapat berkembang dengan baik maka dapat memberikan kontribusi
nyata, seperti terciptanya lapangan kerja, terwujudnya kemajuan pembangunan daerah dan
pembangunan nasional serta memberikan kepercayaan diri dan kebanggaan sebagai negeri
bahari. Namun, menurutnya selama ini pelayaran antar pulau kurang lancar, sehingga
kegiatan ekonomi dan industri lebih banyak berkutat di Pulau Jawa dan sebagian kecil
Sumatera.
tidak optimalnya transportasi laut selain mengakibatkan timpangnya distribusi penduduk
juga mengakibatkan ketimpangan distribusi pembangunan antar daerah. Sekitar 83 persen
dari total aktivitas ekonomi Indonesia terdapat di Sumatera dan Jawa-Bali, sehingga daerah
ini memiliki pendapatan lebih besar dibanding daerah lain. Adanya ketimpangan investasi
sebesar 67 persen yang berada di Jawa dan Sumatera, serta ketimpangan penyebaran industri
di Indonesia yang saat ini sekitar 75 persen dikarenakan sebagian besar sebaran industri
masih bertumpu dan berada di Pulau Jawa.
Sampai saat ini, total 447 Pelabuhan, baik domestic maupun Internasional yang menjadi
infrastrtuktur utama pelayaran nasional. Pelabuhan ini tersebar di seluruh provinsi di
Indonesia dengan alur pelayaran seperti yang tertera dalam Peta pelayaran Nasiobal
Peta Pelayaran Indonesia
Sumber: Dishub.go.id
III. Evaluasi dan Valuasi Ekonomi Transportasi Laut
Prioritaskan Konektivitas Untuk Kawasan Timur
Indonesia
Pembangunan transportasi yang dikaitkan dengan konektivitas demi pemerataan
pertumbuhan ekonomi, mau tidak mau menyinggung Kawasan Timur Indonesia.
Beberapa tahun belakangan ini, Pemerintah secara serius membangun konektivitas
dengan terus menambah jumlah kapal perintis maupun rute-rute baru.
Hal tersebut harus dilakukan mengingat masih banyaknya daerah tertinggal yang ada di
Kawasan Timur Indonesia. Kementerian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
(PPDT), mencatat sebanyak 183 Kabupaten/ Kota masuk kategori kawasan tertinggal di
Indonesia. Sekitar 70 persen, berada di Kawasan Indonesia Timur. Mereka ini struktur
ekonominya didominasi oleh sektor pertanian dan pertambangan, sedangkan
industrialisasi masih belum menonjol. Kemudian masih terjadi disparitas tingkat hidup
dan kemiskinan, kesenjangan pertumbuhan antar wilayah, harga komoditas serta pola
aliran barang yang heterogen baik dari jumlah, jenis maupun arah pergerakan.
Aksesibilitas wilayah tertinggal dan atau pulau terpencil/ terisolasi masih rendah,
frekuensi kunjungan kapal perintis 70 persen dikunjungi sekali dalam 11 hari dan 27
persen sekali dalam 21 hari. “Sebanyak 80,72 persen ruas pelayaran dan pelabuhan
kunjungan dilayani kapal ukuran 750 dan 500 DWT. Kemudian 79,40 persen ruas
pelayaran perintis berjarak kurang dari ≤ 100 sm. Sebagai contoh seperti di daerah
Kabupaten Sangihe Propinsi Sulawesi Utara di mana masyarakat di sana mengeluh tak
menentunya jadwal pelayaran kapal perintis, terutama untuk mereka yang tinggal di
kepulauan.
Asisten Bidang Pemerintahan Pemkab Sangihe, Drs. Christofel Hangau kepada
beritamanado.com, Jumat (8/6/2012) mengungkapkan bahwa, akibat jadwa pelayaran
kapal perintis yang tidak menentu, dampaknya sangat buruk bagi warga yang tinggal di
wilayah kepulauan, karena mereka harus menunggu hingga satu minggu baru bisa
berangkat ke Tahuna. “Padahal, ada empat kapal perintis yang melayani rute pelayaran
ke wilayah Kepulauan Marore, dan sekitarnya, namun karena jadwalnya tidak menentu,
sehingga mempengaruhi aktivitas pemerintahan dan perekonomian warga di sana.
Bayangkan saja, ada pasien rujukan terpaksa dilarikan dengan kapal pump boat yang
berukuran kecil ke Tahuna, karena tidak ada kapal perintis yang masuk,”ujar Hangau.
Hangau menambahkan, bahwa masalah ini mendapat perhatian serius dari Bupati, yang
kemudian meminta kepada pihak Kepala Kantor Penyelenggara Unit II Pelabuhan
Tahuna untuk memfasilitasi dengan pihak manajemen kapal perintis agar ada penetapan
jadwal pelayaran kapal perintis yang melayani rute pelayaran ke wilayah kepulauan
yang ada di Kabupaten Sangihe.
3.1 Kondisi Eksisting dan Potensi Ekonomi Perhubungan Laut
Meningkatnya kinerja investasi yang diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi serta
diharapkan dapat mengatasi masalah penggangguran dan kemiskinan sampai saat ini masih
belum juga terwujud. Menurut beberapa ekonom, lemahnya kinerja investasi disebabkan oleh
dua hal yaitu iklim investasi dan infrastruktur yang belum mendukung dan cenderung buruk.
Dalam tulisan ini akan difokuskan mengenai rendahnya infrastruktur transportasi dalam
kaitannya Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan, mengingat Indonesia adalah
negara yang 70% wilayahnya berupa laut dan terdiri atas 17.500 pulau .
Oleh karena itu transportasi merupakan masalah yang penting, karena transportasi merupakan
gerbang keterisolasian atas wilayah-wilayah yang terpencil dan jauh dari pusat kegiatan
ekonomi. Bahkan selama ini pemerintah daerah yang wilayahnya berupa kepulaunan banyak
mengeluhkan kurangnya sarana transportasi baik transportasi laut maupun udara. Padahal
wilayah tersebut sebenarnya memiliki potensi perekonomian yang cukup tinggi, seperti
misalnya Propinsi Kepulaan Riau, Maluku Utara dan beberapa propinsi lainya memiliki
potensi perikanan dan kelautan yang besar. Namun karena kurangnya sarana transportasi
maka potensi yang ada tersebut belum optimal di kembangkan. Sebagai contoh Maluku Utara
memiliki luas potensi budidaya rumput laut 35.000 ha yang jika dikembangkan akan
menghasilkan sekitar 560.000 ton/th rumput laut kering dengan nilai ekonomi sekitar US$
Interaksi ruang pelayaran perintis yang arahnya cenderung berkembang ke Timur Utara
(region Makassar, Manado, Ambon, Sorong dan Jayapura). Sedangkan untuk interaksi
ke arah timur bagian selatan masih sangat lemah. Terkait dengan karakteristik volume,
jenis muatan dan rasio barang/ kendaraan/penumpang, pelayaran perintis, lokal dan
pelayaran rakyat mempunyai kesamaan ciri dengan angkutan penyeberangan. Maka
yang harus menjadi perhatian adalah terciptanya keterpaduan sistem prasarana dan
sarana pada simpul antar moda transportasi jalan dan transportasi laut/ penyeberangan
supaya dapat meningkatkan efisiensi.
“Kita masih memerlukan peningkatan integrasi inter dan antarmoda, prasarana/ sarana
dan karakteristik muatan, penataan pola trayek dengan prinsip the right route and the
right type of ship dan triple output (ekonomi, sosial dan lingkungan). Untuk
meningkatkan efektifitas dan efisiensi layanan, perlu ditata keterpaduan dan hierarki
semua moda angkutan terkait (armada PT Pelni, perintis laut dan penyeberangan, kapal
cepat milik daerah dan swasta),” kata Prof Dr.-Ing. Mohammad Yamin Jinca, M.S.Tr.,
KPS Transportasi PPs Universitas Hasanudin
Sumber: TRANS Media Edisi 06/2012 : Peluang Indonesia Dalam Transportasi Dunia
Majalah Kementerian Perhubungan
No.STT. No. 349 SK/Ditjen PPG/STT 1976
ISSN : 0853179X
280 juta, nilai ini tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada sarana pengangkutan untuk ekspor
maupun distribusi ke wilayah yang memiliki industri pengolahan rumput laut (Dahuri, 2009).
Oleh karena itu sarana transportasi merupakan sesuatu yang penting dalam rangka
meningkatkan kinerja pembangunan dan investasi. Jika di wilayah tersebut dibangun sarana
transportasi maka investor tidak akan segan-segan menamankan modalnya untuk
pengembangan budidaya rumput laut di Maluku Utara atau wilayah lain yang memiliki
potensi sumberdaya kelautan dan perikanan.
Dengan demikian tujuan pembangunan transportasi (terutama transportasi laut) antar pulau-
pulau bagi bangsa Indonesia adalah untuk mewujudkan perhubungan laut sebagai urat nadi
kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, sarana untuk
memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta sebagai penyedia lapangan kerja dan penghasil
devisa negara.
Pengadaaan infrastruktur transportasi memiliki peran besar dalam perkembangan
perekonomian bangsa Indonesia. Dalam hal ini perhubungan laut berperan dalam
memperlancar perpindahan barang dan jasa dari satu pulau ke pulau yang lain, mempercepat
transaksi perdagangan dan proses ekspor dan impor dari suatu wilayah, baik dalam maupun
luar negeri.
Berdasarkan data yang ada, hampir 80 % lebih proses perpindahan barang dan jasa antar
pulau menggunakan jasa perhubungan laut. Berdasarkan hal tersebut dapat kita bayangkan
bahwa sektor kegiatan perhubungan laut merupakan salah satu penunjang utama dalam
pergerakan ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan suatu kawasan (Dahuri, 2009)
Sektor transportasi sangat berpengaruh dalam mempercepat pergerakan ekonomi di suatu
wilayah, oleh karena itu perlu segera dibangun infrastruktur transportasi terutama dalam
penyelenggaraan perhubungan laut sehingga akan terselenggara jaringan transportasi yang
profesional dalam melayani jasa transportasi di laut.
Begitu pentingnya peran trasportasi, sehingga dapat dibayangkan bagaimana jadinya apabila
jasa transportasi antar pulau tidak berjalan atau berhenti, berapa banyak kerugian materil
maupun non-materil yang akan diderita baik oleh perorangan, swasta, pengusaha, BUMN
maupun lembaga pemerintah.
Oleh karena itu, perlu disiapkan segera infrastruktur transportasi sehingga pendayagunaan
potensi ekonomi di wilayah kepulauan dapat dimanfaatkan secara optimal. Untuk dapat
mewujudkan hal tersebut maka perlu dilakukan terobosan untuk membangun infrastruktur
transportasi dan salah satunya adalah dengan kerjasama saling menguntungkan antara
pemerintah dan swasta, hal ini dilakukan dalam mengatasi masalah minimnya anggaran untuk
pembangunan infrastruktur. Langkah pembangunan infrastruktur perlu mendapat dukungan
dari seluruh stakeholders baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.
Dengan demikian akan segera terwujud infrastruktur transportasi yang memadai sehingga
perekonomian di wilayah kepulauan dapat segera berkembang sehingga masalah
penggangguran dan kemiskinan dapat segera teratasi.
Potensi perhubungan laut diperkirakan sebesar US$30 miliar/tahun. Ini berdasarkan pada
perhitungan bahwa sejak 15 tahun terakhir kita mengeluarkan devisa sekitar US$ 15
miliar/tahun untuk membayar armada pelayaran asing yang mengangkut 97% dari total
barang yang diekspor dan diimpor ke Indonesia, dan yang mengangkut 50% total barang
yang dikapalkan antar pulau di wilayah Indonesia (Kompas, 2013)
Belum lagi potensi ekonomi dari industri dan jasa maritim (seperti galangan kapal, coastal
and offshore engineering, pabrik peralatan dan mesin kapal serta perikanan, dan teknologi
komunikasi dan informasi), pulau-pulau kecil, dan SDA non-konvensional yang sangat besar.
Bila Indonesia mampu meningkatkan kemampuannya dalam industri dan jasa maritim setara
Korea Selatan dan Singapura, maka potensi ekonominya dapat mencapai sekitar US$ 4
Triliun per 10 tahun pembangunan (Kompas, 2013)
Menurut Bobby, kondisi transportasi laut ini memang harus didukung oleh sistem transportasi
yang cepat dan murah. Sistem transportasi ini juga harus didukung oleh sarana transportasi
laut seperti kapal laut, pelabuhan hingga urusan sumber daya manusia (SDM). Apalagi
program MP3EI itu harus didukung oleh transportasi laut.
Saat ini, pemerintah terus menyinergikan antara sistem transportasi di kawasan Indonesia
Timur dan Indonesia kawasan Barat. Sehingga konektivitas antarpulau di Indonesia ini akan
berlangsung baik. Sejauh ini, konektivitas ini hanya berdasarkan satu dua pulau saja dan
belum bisa menyinergikan antara pulau di kawasan Timur dengan kawasan Barat. Hal Ini
yang harus dirasa perlu untuk didukung oleh seluruh otoritas (Kompas, 2013)
Untuk nilai investasinya, menurut Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian
Perhubungan Bambang S Ervan menjelaskan pemerintah akan mendatangkan 14 unit kapal
Roro dengan total investasi mencapai Rp 400 miliar. Untuk satu unit kapal harganya sekitar
Rp 30 miliar- Rp 35 miliar dengan kapasitas 75 Gross Ton (Kompas, 2013)
Untuk empat kapal perintis, terdiri dari satu unit kapal berukuran 750 Deadweight Ton
seharga Rp 24 miliar, satu unit kapal berukuran 500 Deadweight Ton seharga Rp 20,4 miliar
dan dua unit kapal 1.200 Deadweight Ton total nilai Rp 95,4 miliar (Kompas, 2013)
3.2 Nilai Ekonomi Pelabuhan Bangsal – Gili Matra, Kabupaten Lombok
Utara
Perhubungan laut menjadi media konektivitas dan interaksi sosial, ekonomi, dan budaya
dengan tujuan untuk pembangunan berkelanjutan daerah. Pelabuhan Bangsal terletak di
Kecamatan Pemenng, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jika melihat
dari kategori pelabuhan dengan tinkat yang dilayani, maka Pelabuhan Bangsal termasuk
dalam kategori pelabuhan lokal, karena hanya melayani akses transportasi laut menuju Gili
Matra, yang merupakan penyumbang pemasukan ekonomi terbesar dari sector pariwisata di
Kabupaten Lombok Utara. Dari segi pelayaran, Pelabuhan Bangsal termasuk pelabuhan
melayani pelayaran lokal. Gili Matra merupakan nama lain dari Desa Gili Indah, yang terdiri
dari Dusun Gili Air, Dusun Gili Meno, dan Dusun Gili Trawangan, dimana ketiganya
merupakan Dusun Pulau dan terpisah satu sama lainnya
Gili Matra (Desa Gili Indah)
Secara Geografis Wilayah Desa Gili Matra merupakan bagian dari wilayah administratif
Pemerintahan Kecamatan Pemenang. Desa Gili Indah berbentuk kepulauan yang terdiri dari
tiga pulau kecil yang disebut dengan Gili, terletak dibagian utara Kecamatan Pemenang
dengan batas wilayah adalah sebagai berikut:
Batas Sebelah Utara : Laut Jawa
Batas Sebelah Timur : Laut Sira
Batas Sebelah Selatan : Desa Pemenang Barat dan Malaka
Batas Sebelah Barat : Selat Lombok
Luas Wilayah : 678 Ha diantaranya:
Dusun Gili Air : 188 Ha
Dusun Gili Meno : 150 Ha
Dusun Gili Trawangan : 340 Ha
Kantor Desa Gili Indah berada di Dusun Gili Air. Jarak antar dusun dapat ditempuh dengan
menggunakan perahu ataupun boat yang terdapat pada masing-masing Dusun dan
membutuhkan waktu sekitan ±15 menit perjalanan laut.
Tabel Pembagian Wilayah Administrasi Desa
No Dusun Jumlah
RT
Jumlah Luas
(Ha) KK Jumlah Penduduk
Laki-laki Perempuan
1 Gili Air 6 418 790 750 188
2 Gili Meno 4 165 261 273 150
3 Gili
Trawangan 7 352 740 747 340
Total 935 1.791 1.770 678
Sumber : Profil Desa Gili Indah, 2011
Kehidupan Sosial Masyarakat Gili Matra
Seirng bertambahnya waktu, masyarakat Gili matra turut mengalami perubahan mata
pencaharian. Beberapa perubahan dilakukan karena merasa lebih bisa mencukupi kebutuhan
sehari-hari, namun tidak jarang perubahan terjadi karena mata pencaharian sebelumnya tidak
dapat dilakukan lagi, atau pendapat menurun dari mata pencaharian yang sama.
Tabel Perubahan Mata pencaharian Masyarakat Gili Matra
Pertanyaan Jawaban
Dulu (tahun 90-an) Sekarang (tahun 2000-an)
Sumber penghidupan utama (mata pencaharian) dan tambahan
Berkebun (P/L)
Ternak (P/L)
Buat perahu (L)
Jual ikan (P)
TKI (L)
Budidaya rumput laut (P/L)
Laundry (P)
TKI (L)
TKW (P)
Nelayan (L)
Jual ikan (P)
Buat perahu (L)
Ternak (P/L)
PNS (guru pariwisata) (P/L)
Pariwisata dan perhotelan (P/L)
Buruh bangunan (L)
Guide (L)
Bakulan keliling: jual ikan, sayur, kue (P)
‘buruh’ swasta; angkat barang (P/L)
Sumberdaya tumpuan masyarakat
Laut
Pariwisata
TKI
Dagang
Kebun
Pertenakan
Laut
Pariwisata
TKI
Dagang
Kebun
Pertenakan
Apakah kegiatan yang dikerjakan laki-laki dan perempuan atas penghidupan dan SDA
Membajak (L)
Berkebun (L/P)
Beternak (P/L)
Nelayan (L)
Membajak (L)
Berkebun (L/P)
Beternak (L/P)
Melaut (L)
Jual ikan (P) Jual ikan (P)
Buruh (L/P)
Gaid (L)
Bakulan keliling (P)
Pihak mana yang berwenang memberi izin menggunakan sumberdaya
Tidak ada
Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara
Pemerintah Desa (awik-awik)
Perubahan kondisi sumber daya alam
Lahan berkebun banyak
Ternak banyak
Melaut bebas
Ikan banyak
Dulu air tawar ada (sumur)
Sudah berubah bangunan dan dimiliki oleh orang luar
Ternak berkurang
Melaut terbatas
Ikan berkurang (sekarang terbatas)
Air payau dan asin (sumur)
Perubahan pada cara masyarakat memanfaatkan SDM
Melaut sekitar pulau
Perahu pake layar dan dayung
Alat tangkap jaring dan dayung
Melaut jauh sampai ke perbatasan bali
Pakai mesin
Alat tangkap jaring dan panah
Perubahan pada kehidupan sosial ekonomi masuk 10 tahun terakhir
Hubungan masyarakat pulau sederhana dan penuh kekeluargaan
Rabu bontong (mandi sapar)
Pendapatan nelayan banyak, yang miskin bisa kaya
Individu
Rabu bontong (mandi sapar)
Pendapatan nelayan semakin berkurang
Yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin terutama yang kaya hanya pegawai pemerintah desa.
Perubahannya lainnya
Terdapat usaha pariwisata laut dan pantai
Sektor pariwisata maju dengan pesat.
Sumber: I-CATCH Desa Gili Indah, 2012
Keterangan: P adalah Perempuan; L adalah Laki-laki
Berdasarkan data di atas, sumber utama penghidupan masyarakat Desa Gili Indah pada tahun
rentang tahun 1990 adalah nelayan tradisional dengan alat tangkap yang sederhana dan
menggunakan perahu kecil yang seadanya. Pada tahun 1996/1997 masyarakat juga
melakukan budidaya rumput laut. Hasil dari budidaya rumput laut mampu meningkatkan
perekonomian masyarakat jauh dibandingkan saat ini, walaupun mata pencaharian saat ini
lebih variatif (petani, PNS, swasta, pedagang, dan membuka usaha sendiri).
Dalam jangka waktu kurang lebih 30-40 hari, pertumbuhan rumput laut dengan metode long
line sederhana tersebut sangat bagus (dapat segera di panen). Semenjak saat itu semua
masyarakat turut mengembangkan dan membudidayakan rumput laut. Namun, budidaya
rumput laut hanya dapat dilaksanakan selama satu tahun saja, dikarenakan rumput laut yang
ditanam (dibudidayakan) masyarakat terserang penyakit ice-ice (bahasa lokal), dengan
ditandai thallus (jaringan yang masih belum bisa dibedakan bagian-bagiannya, yang
membentuk tubuh rumput laut) rumput laut memutih, layu dan kemudian mati. Berbagai cara
dan upaya telah dilakukan untuk mengatasi penyakit tersebut, namun jumlah rumput laut
justru semakin berkurang. Sejak saat inilah masyarakat sudah tidak melakukan kegiatan
budidaya rumput laut lagi.
Selain sebagai nelayan dan pembudidaya rumput laut, pekerjaan lain yang dilakukan oleh
masyarakat adalah peternak sapi dan kuda, buruh tani, buruh bangunan, pembuat kerajinan,
pembuat perahu dan beberapa pekerjaan lainnya. Akan tetapi, pekerjaan tersebut hanya
sebagai pekerjaan sampingan saja dan hanya dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat saja.
Pada tahun 1990-an, masyarakat tidak dibatasi oleh aturan dan tidak harus meminta ijin pada
siapapun ketika melaut. Mereka menangkap ikan dengan bebas tanpa ada aturan yang
mengikat. Pada tahun 2000-an nelayan sudah tidak bisa melaut dengan bebas dikarenakan
Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Pemerintah Pusat menjadikan Desa
Gili Indah menjadi salah satu wilayah konservasi yang harus dijaga dan dilestarikan lautnya.
Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah malakukan Perencanaan Pengelolaan
wilayah laut Desa Gili Indah dengan menggunakan sistem zonasi, diantaranya zona inti, zona
perikanan berkelanjutan, serta zona pemanfaatan dan zona lainnya. Beberapa masyarakat
merasa dirugikan atas rencana pengelolaan zonasi yang dirasa sangat membatasi. Di sisi lain,
dengan adanya rencana zonasi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah KLU dan Pemerintah
Pusat sekaligus melakukan pelestarian terumbu karang terus dilakukan hingga saat ini,
dengan cara melakukan budidaya terumbu karang dengan berbagai metode budidaya, seperti
transplantasi (cangkok terumbu karang) dan biorock di Gili Trawangan. Biorock merupakan
pelestarian terumbu karang dengan mengunakan media tanam seperti, yang kemudian dialiri
listrik searah dengan voltase rendah (I-CATCH Desa Gili Indah, 2012).
Biorock di Gili Trawangan
Pembatasan pemanfaatan akses sumber daya laut dapat mempengaruhi hasil tangkapan
nelayan secara langsung, yang secara otomatis akan berpengaruh terhadap tingkat
perekonomian masyarakat. Akibatnya, tidak sedikit masyarakat yang beralih profesi menjadi
pekerja pariwisata (swasta) diantaranya menjadi pegawai Resort, Villa maupun restaurant.
Sebagian dari masyarakat menjadi ‘buruh’ angkat barang wisatawan. Tidak jarang ibu-ibu
juga bekerja sebagai tukang cuci pakaian (laundry) dengan harga Rp. 20.000,- hingga
Rp.25.000,-/kg. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat Desa Gili Indah merupakan
langkah alternaif terhadap pembatasan akses terhadap sumber daya laut, dimana kegiatan-
kegiatan ini dapat membantu masalah ekonomi masyarakat. Hingga saat ini, masyarakat
sudah terbiasa dengan kondisi tersebut, bahkan kegiatan-kegiatan yang pada awalnya
merupakan pekerjaan alternatif, kini sudah menjadi pekerjaan utama. Dengan adanya kondisi
ini, jumlah nelayan semakin berkurang, dan diperkirakan dalam kurun waktu 10-20 tahun
terakhir, pendapatan para nelayan semakin menurun.
Pada tahun 1990-an, masyarakat masih melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan
bom. Saat ini sudah tidak ada lagi masyarakat yang menangkap ikan dengan menggunakan
bom, karena sudah ada aturan atau awik-awik (aturan adat yang dibuat oleh masyarakat desa)
untuk tidak menangkap ikan dengan cara pengeboman, yang telah disepakati oleh Pemerintah
Desa dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara. Jika ada terdapat pemalnggaran
(masih menangkap menunakan bom), maka masyarakat yang melangar akan dijatuhi sanksi
yang sudah disepakati bersama (terdapat beberapa kesepakatan bersama, salah satunya
adalah dikeluarkan dari wilayah Desa Gili Indah).
Berdasarkan pengamatan fisik oleh masayrakat yang bermata pencaharian sebaai nelayan,
jumlah ikan dirasa semakin berkurang. Hal ini berbanding terbalik dengan semakin tingginya
biaya operasional (harga bahan bakar) dan maintenance peralatan (mesin sampan). Beberapa
nelayan berharap adanya bantuan sarana dan prasarana alat tangkap yang memadai dan
adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Berdasarkan hasil diskusi, terjadi perubahan pada kehidupan sosial ekonomi dalam 10 tahun
terakhir. Pada tahun 1990-an, masyarakat Desa Gili Indah memiliki pola pikir yang
sederhana dan rasa kekeluargaan yang kuat. Setiap hari rabu bontong (hari rabu di minggu ke
empat pada bulan Safar dalam kalender Masehi), masyarakat melakukan gotong-royong
untuk membersihkan laut (ritual mandi sapar). Pada tahun 2000-an, suasana kekeluargaan
sudah semakin menurun dan rabu bontong (mandi sapar) sudah jarang dilakukan dikarenakan
dana untuk melaksanakan kegiatan tersebut semakin tinggi, sedangkan pendapatan nelayan
semakin berkurang, sementara masyarakat lainnya sudah berubah pola pikir dengan hanya
menguntungkan dirinya sendiri (individu).
Perubahan lain yang terjadi, yaitu usaha pariwisata laut dan pantai meningkat dengan pesat
dari tahun ke tahun. Kepemilikan lahan lebih banyak dikuasai oleh pihak asing (warga negara
asing).
Dampak TWALGM terhadap kehidupan Ekonomi Masyarakat Desa Gili Indah (GIli
Matra)
Menteri kehutanan dengan Surat keputusan nomor 85 tahun 1993, telah menetapkan kawasan
GIli Matra sebagai salah satu Taman Nasional dengan luas 2,954 hektar, yang dikenal dengan
Taman Wisata Alam Laut Gili Matra (TWALGM). Namun demikian, kegiatan pertambangan
karang dan penangkapan ikan dengan bahan peledak masih berlangsung sehingga telah
mengakibatkan kerusakan lingkungan terumbu karang yang signifikan, meskipun serangkaian
program partisipasi masyarakat dan beberapa kebijakan telah dikeluarkan.
Data survey yang dilakukan Yakin (2005) pada tahun 2007 menunjukkan bahwa profesi
nelayan dan bekerja pada sektor pariwisata merupakan sumber penghasilan sebagian besar
masyarakat sekitar Kawasan Gili Indah. Jika dilihat dari segi pendapatan rata-rata
berdasarkan jenis pekerjaan, data pada tabel dibawah juga menunjukkan bahwa pekerjaan
pada bidang perhotelan dan restoran, pramuwisata/guide, pedagang dan usaha angkutan baik
ojek, cidomo, maupun perahu motor. Sementara itu mereka yang memiliki pekerjaan
sampingan adalah relatif kecil yaitu hanya sebesar 10 %. Selanjutnya, peran Ibu rumah
tangga dan wanita tidak kalah pentingnya dalam keluarga termasuk dalam kontribusinya
terhadap ekonomi keluarga.
Hasil survei terhadap jenis pekerjaan ibu rumahtangga dan wanita menunjukkan bahwa
tingkat partisipasi wanita pada pekerjaan atau mencari nafkah keluarga adalah relatif kecil
atau 18%, sedangkan sisanya (82 persen) hanya bekerja sebagai ibu rumahtangga. Jenis- jenis
pekerjaan di mana mereka terlibat adalah berdagang, pegawai cafe/restoran/hotel, berkebun
dan koki. Kedepan perlu ada program yang jelas bagi pemberdayaan perempuan melalui
pendidikan dan latihan terutama yang terkait dengan pengembangan pariwisata di kawasan
Gili Indah sehingga keberadaannya memberikan manfaat bagi wanita dan masyarakat secara
keseluruhan.
Tebel Jenis Pekerjaan dan pendapatan perbulan masyarakat Desa GIli Indah
Sumber: Yakin, 2005
Berdasarkan data BPS (2005), kontribusi sektor-sektor yang terkait dengan pariwisata ini
terhadap ekonomi kecamatan Pemenang dimana kawasan TWALGM berada relatif tinggi
yaitu mencapai 48,33%. Oleh karena itu, keberadaan kawasan ini telah berdampak positif
terhadap perekonomian daerah. Sebagai daerah obyek wisata, ketersediaan sarana
perdagangan dan pariwisata di kawasan TWALGM ini adalah sangat tinggi, yaitu dari 107
hotel/penginapan yang ada di kecamatan Pemenang, 104 di antaranya berlokasi di desa Gili
Indah. Berbagai jenis hotel yang ada memiliki tarif bervariasi yaitu dari Rp. 50.000 per
malam sampai Rp. 5.000.000 per malam tergantung dari kondisi dan fasilitas yang tersedia.
Tabel Interaksi Ekonomi Masyarakat dengan Gili Indah, 2007
Selain itu, rumah makan dan restoran di wilayah ini sudah menyediakan menu makanan dan
minuman Barat dan local. Fasilitas lain yang tersedia adalah rental kaset, VCD/DVD serta
took-toko souvenier. Terdapat juga fasilitas internet yang bisa digunakan oleh wisatawan
untuk berkomunikasi dengan dunia luar (maya). Selain itu terdapat bisnis di bidang jasa
snorkeling dan diving, yaitu yang dikelola oleh dream divers dan Blue Marlien Dive, yang
kesemuanya menambah daya tarik kawasan ini.
Aturan mengenai sarana trasportasi yang boleh dioperasikan di Gili adalah bahwa kendaraan
bermotor baik roda dua maupun roda empat dilarang beroperasi di kawasan Gili, sehingga
sarana transportasi yang tersedia adalah hanya cidomo dan sepeda. Selain untuk memberikan
peluang usaha bagi penduduk setempat, kebijakan ini dilakukan untuk meng-hindari polusi
kendaraan bermotor dan melestarikan budaya setempat. Bagi yang ingin menaiki cidomo
untuk mengitari wilayah luar dari Gili Terawangan misalnya, pengunjung bisa menyewa
sekali puturan dengan biaya antara Rp. 35.000,- sampai Rp. 50.000,- tergantung tawar-
menawar dan kondisi kunjungan. Pada saat kunjungan yang sangat padat, biayanya tidak bisa
kurang dari Rp. 50.000,- per satu kali keliling. Pendapatan kotor mereka dari usaha angkutan
cidomo cukup lumayan tinggi yaitu berkisar antara Rp. 100.000 sampai dengan Rp 300.000
per hari. Ada yang menarik dari operasi cidomo ini yaitu 1 cidomo hanya boleh menaikkan
penumpang maksimum sebanyak 3(tiga) orang. Jika penumpangnya lebih, maka kusir atau
pemilik cidomo akan dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- dan tidak boleh beroperasi
selama 1 minggu. Selain itu, pengunjung atau wisatawan di Gili Terawangan bisa menyewa
sepeda dengan biaya sekitar Rp. 25.000,- per hari yang bisa digunakan untuk menikmati
pemandangan sekitar kawasan Gili Indah.
Besarnya nilai ekonomi pariwisata kawasan TWALGM sangat ditentukan oleh jumlah
wisatawan yang datang baik wisatawan domestik maupun mancanegara, lama tinggal, jenis
hotel dan akomodasi yang dipilih, jenis transportasi, dan konsumsi lainnya. Data BPS (2005)
menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan ini cukup tinggi yaitu mencapai
85140 orang yaitu terdiri dari wisatawan mancanegara (ASEAN, Asia, Eropah, Amerika,
Oceania, dan Afrika) sebanyak 69477 orang (81,60%) dan sisanya sebanyak 15.663 orang
(18,40 %) merupakan wisatawan domestik.
Seluruh wisatawan asing menginap di kawasan Gili Indah. Dengan menggunakan biaya
perjalanan per kapita dari hasil kajian WWW (2001) oleh wisatawan (mancanegara dan
domestic) selama tinggal di Pulau Lombok adalah sebesar Rp. 345 860, maka potensial
nilai ekonomi pariwisata di kawasan TWALGM mencapai Rp. 29.447.031.240,- per tahun.
Dalam hal ini, jika pemerintah menetapkan tiket masuk (entry fee) bagi setiap pengunjung ke
kawasan TWALGM maka menghasilkan dana yang signifikan bagi pelestarian sumberdaya
perairan laut dan pesisir di kawasan TWALGM tersebut.
Pelabuhan Bangsal
Mega proyek pembangunan pelabuhan di Kabupaten Lombok Utara (KLU) sepenuhnya
dibantu pusat melalui APBN. Dua pelabuhan yang sedang dibangun itu adalah Pelabuhan
Bangsal di Kecamatan Pemenang dan Pelabuhan Carik di Bayan. Untuk Pelabuhan Bangsal,
pada tahun 2011 lalu pemerintah pusat memberikan dana Rp 20 miliar yang digunakan untuk
proses reklamasi, pengembangan dermaga dan pembangunan fasilitas pelabuhan. Proyek
pelabuhan yang menjadi pintu masuk ke kawasan tiga gili itu dikerjakan oleh pusat melalui
Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Lombokpost, 2011)
Sementara untuk dermaga di Gili Trawangan, Meno dan Air, akan membangun dermaga
apung. Sehingga dengan keberadaan dermaga apung itu memberikan kenyamanan bagi para
pengunjung termasuk juga pengusaha angkutan laut
Jumlah armada yang beroperasi di kawasan wisata ini adalah sebanyak 52 unit, terdiri
dari 25 unit (48%) yang menuju Gili Air, yang ke Gili Meno sebanyak 10 unit (19%), dan
yang ke Gili Trawangan 17 unit (33%). Data tersebut menunjukkan bahwa keberadaan
angkutan Pelra terbanyak adalah yang menuju Gili Air (48%). Berdasarkan data survey,
diperoleh: waktu tempuh yang diperlukan untuk menyeberang dari Bangsal menuju Gili Air
adalah sekitar 15 menit, ke Gili Meno 25 menit, dan yang ke Gili Terawangan sekitar
30 menit. Kondisi ini belum mencerminkan keseimbangan yang harmonis antara keinginan
dan kebutuhan pengguna jasa dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di
kawasan ini.
Selanjutnya, Munawar (2005) menyatakan bahwa salah satu solusi yang dapat
dilakukan adalah dengan regulasi yang jelas terhadap eksistensi angkutan umum, yang
menyangkut: Pembatasan dan efisiensi jumlah armada, dimaksudkan agar tercapai load
factor ideal, sehingga kelangsungan pengusaha angkutan umum dapat terjamin, untuk itu
perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui berapa Load factor dan jumlah permintaan
(demand) angkutan penyeberangan di kawasan wisata ini baik lintas Bangsal – Gili Air,
lintas Bangsal – Gili Meno, maupun lintas Bangsal – Gili Trawangan.
Angkutan penyeberangan yang beroperasi di kawasan wisata terpadu Gili Pemenang
Lombok Utara, yang digunakan oleh masyarakat baik masyarakat domestik maupun
masyarakat mancanegara adalah angkutan Pelayaran rakyat (Pelra) yang berupa perahu
motor yang memiliki performansi kapal sederhana dan bermesin tempel.
Dari segi headway (interval waktu kedatangan) angkutan penyeberangan ini waktu tunggunya
cukup lama, hal ini ditunjukkan dengan satu angkutan yang hanya beroperasi dua kali
dalam sehari jika permintaan cukup ramai. Jadi jika armada tersebut mulai beroperasi
dari jam 08.00-17.00 wita, maka dalam jangka waktu tersebut ada 540 menit, yang
berarti headway penumpang adalah:
a) Lintas Bangsal - Gili Air sekitar 540 menit/(2 x 25) = 10,8 menit = 11 menit
b) Lintas Bangsal - Gili Meno headwaynya 540 menit/(2 x 10) = 27 menit
c) Lintas Bangsal - Gili Trawangan 540 menit/(2 x 17) = 16 menit.
Hal ini menunjukkkan bahwa headway nya cukup lama, dimana headway ideal 5 – 10
menit (Nasution, 1996), sehingga calon penumpang menunggu cukup lama untuk dapat
menggunakan angkutan penyeberangan ini. Pada penelitian yang dilakukan Rohani Tahun
2006 diperoleh kemampuan membayar (ATP) pengguna angkutan pelayaran rakyat di
kawasan wisata Gili Pemenang Lombok Utara adalah sebesar 94,93%, dan kemauan
membayarnya (WTP) adalah 64,63% (Rohani dan Hasyim, 2006). Jika dilihat dari ATP dan
WTP yang diperoleh menunjukkan bahwa kemauan dan kemampuan membayar
pengguna angkutan pelayaran rakyat cukup tinggi.
Tarif yang berlaku di kawasan wisata ini adalah: Rp 8.000,- untuk lintas Bangsal -
Gili Air, Rp 9.000,- lintas Bangsal - Gili Meno, dan lintas Bangsal - Gili Trawangan Rp
10.000,-. Tarif ini sudah mulai diberlakukan sejak tahun 2005 sampai tahun 2012.
Kegiatan yang bercirikan profeet oriented (berorientasi pada keuntungan), selalu
menekankan apakah dan sampai sejauh mana kegiatan tersebut memberikan benefit yang
lebih besar dari biaya kepada yang mengadakan. Atau apakah aktifitas tersebut membawa
benefit bersih dari segi penyelenggaranya. Untuk itu perlu dibandingkan arus benefit
dengan arus biayanya (Kadariah, Karlina dan Gray, 1999). Pendapatan angkutan umum dapat
dihitung dari: tarif per trip, load factor dan jumlah trip yang dilakukan.
Fakta yang ada menunjukkan bahwa kondisi yang ada saat ini dengan ATP yang cukup
tinggi 94,93% (Rohani dan Hasyim, 2006), angkutan pelayaran rakyat (Pelra) belum bisa
membawa benefit bersih kepada penyelenggaranya karena adanya kenaikan harga diberbagai
sektor yang berakibat kenaikan cost (biaya operasional).
Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terkait penetapan tarif angkutan agar
mendapatkan optimum benefit, yaitu dengan cara:
1. Analisa Permintaan
Permintaan (demand) adalah banyaknya barang dan manusia yang akan dipindahkan
dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu satu jam. Besarnya arus penumpang yang
ada dapat dihitung dengan rumusan sebagai berikut:
Dengan:
Q = arus penumpang per jam
f = frekuensi kendaraan per jam
p = kapasitas kendaraan
h = headway (h dalam jam)
LF = load factor
Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap jumlah permintaan tersebut di atas dapat
dijelaskan sebagai berikut: (Teknomo K. dan Irawan R., 1997)
a. Faktor muat (Load Factor)
Faktor muat (Load factor) dianalisis untuk mengetahui jumlah penumpang dibagi
dengan ketersediaan tempat duduk pada angkutan penyeberangan. Besarnya faktor
muat dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut :
b. Waktu antara (headway)
Waktu antara (headway) diperoleh dengan mengukur selisih waktu keberangkatan
angkutan penyeberangan pertama dengan angkutan penyeberangan
berikutnya, yang dirumuskan sebagai berikut :
dengan:
h = headway (h dalam jam)
t1 = waktu keberangkatan kendaraan pertama
t2 = waktu keberangkatan kendaraan kedua
c. Frekuensi Kendaraan Perjam
Frekuensi (f) yaitu jumlah kendaraan yang lewat per satuan waktu. Frekuensi
dihitung dengan rumus:
2. Parameter dan Perhitungan Pendapatan
Parameter dan perhitungan pendapatan dan biaya operasi adalah sebagai berikut
(Nasution, 1996):
a. Pendapatan/ benefit angkutan umum
Besarnya pendapatan (Benefit) angkutan umum adalah merupakan perkalian antara
jumlah penumpang dengan tarif per penumpang. Sehingga untuk satu angkutan,
besarnya pendapatan adalah:
b. Biaya operasional/cost angkutan umum
1. Biaya tetap adalah biaya yang terjadi pada awal dioperasikannya angkutan
yang terdiri dari biaya penyusutan; biaya perizinan dan administrasi, sehingga
besarnya biaya tetap dihitung dengan rumus:
Dengan:
Bpk = biaya penyusutan
Bpa = biaya perizinan dan administrasi
Biaya penyusutan adalah biaya yang dikeluarkan atas penyusutan nilai angkutan.
Sedangkan biaya perizinan dan administrasi mencakup biaya Surat Tanda
Kendaraan Bermotor (STNK), biaya Bea Balik Nama (BBN), biaya izin
perangkutan.
2. Biaya tidak tetap
adalah biaya yang dikeluarkan pada saat suatu angkutan beroperasi. Biaya
tidak tetap (variable cost) sangat bervariasi yang terdiri dari: biaya bahan bakar,
pemakaian oli/pelumas, biaya perawatan dan perbaikan, biaya operator/ awak.
Besarnya biaya tidak tetap untuk setiap tahunnya adalah sebagai berikut:
Dengan:
Bbbm = biaya bahan bakar minyak
Bpom = biaya pemakaian oli/pelumas
Bpp = biaya perawatan dan perbaikan
Bgok = biaya operator/ awak
Kelayakan operasional angkutan umum dari sisi finansial dapat diketahui berdasarkan
Pendapatan dan Biaya Operasi atau dengan perbandingan Benefit (B) dan Cost (C). Jika
digunakan asumsi bahwa benefit netto pengelola angkutan 10%, maka Benefit (B)
berbanding Cost (C) minimal 1,1.
Pustaka
Indonesia-Climate Adaptation Tools for Coastal Habitat (I-CATCH). 2012. Kajian
Kerentanan Dampak Perubahan Iklim Desa Gili Indah. IMACS: USAID
Munawar, A., 2005. Dasar-Dasar Teknik Transportasi. Penerbit Beta Offset: Jogjakarta.
Nasution, H.M.N., 1996, Manajemen Transportasi. Penerbit Ghalia: Jakarta
Profil Desa GIli Indah 2012
Rohani, dan Hasyim., 2006. Analsis Ability To Pay (ATP) dan Willingness To Pay (WTP) Di
Kawasan Wisata Terpadu Gili Pemenang Lombok Barat. Laporan Penelitian
dengan biaya Ditjen Dikti-Depdiknas, Dosen Muda , Universitas Mataram
Suyono, R.,P. 2003. Shipping: Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut, Edisi
Revisi. Victoria Jaya Abadi: Jakarta
http://id.wikibooks.org/wiki/Moda_Transportasi diakses pada tanggal 1 Desember 2013
http://exploredia.com/biggest-ship-in-the-world-2011/ diakses pada tanggal 1 Desember 2013
http://www.antaranews.com/berita/300200/transportasi-laut-miliki-peran-penting-dalam-
pembangunan-nasional diakses pada tanggal 1 Desember 2013
http://rokhmindahuri.wordpress.com/tag/transportasi-laut/ diakses pada tanggal 1 Desember
2013
http://www.lombokpos.co.id/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=62%
3Aadministrator&Itemid=28&limitstart=1900 diakses pada tanggal 1 Desember
2013
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/02/22/09151181/Transportasi.Laut.Akan.Diper
kuat diakses pada tanggal 2 Desember 2013