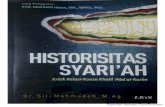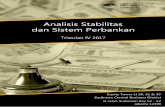UNIVERSITAS INDONESIA PERAN PERBANKAN SYARI'AH ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of UNIVERSITAS INDONESIA PERAN PERBANKAN SYARI'AH ...
UNIVERSITAS INDONESIA
PERAN PERBANKAN SYARI’AH DALAM PENGELOLAAN
WAKAF UANG
TESIS
MOH. ANIQ KAMALUDDIN
NIM:1206183905
F A K U L T A S H U K U M
PROGRAM MAGISTER HUKUM
HUKUM EKONOMI ISLAM
J A K A R T A
JULI 2 0 1 4
ii
Universitas Indonesia
UNIVERSITAS INDONESIA
PERAN PERBANKAN SYARI’AH DALAM PENGELOLAAN
WAKAF UANG
TESIS
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.)
MOH. ANIQ KAMALUDDIN
NIM:1206183905
F A K U L T A S H U K U M
PROGRAM MAGISTER HUKUM
HUKUM EKONOMI ISLAM
J A K A R T A
JULI 2 0 1 4
iii
Universitas Indonesia
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS
Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.
Nama : Mohammad Aniq Kamaluddin
NPM : 1206183905
Tanda Tangan :
Tanggal : 4 Juli 2014
iv
Universitas Indonesia
HALAMAN PENGESAHAN
Tesis ini diajukan oleh:
Nama : Mohammad Aniq Kamaluddin
NPM : 1206183905
Program Studi : Ilmu Hukum (Hukum Ekonomi Islam)
Judul Tesis : Peran Bank Syari’ah Dalam Pengelolaan Wakaf Uang
Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima
sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas
Indonesia.
DEWAN PENGUJI
Pembimbing : Farida Prihatini, S.H., M.H., CN ( )
Penguji : Prof. Dr. Uswatun Hasanah ( )
Penguji : Neng Djubaedah, S.H., M.H, Ph.D. ( )
Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 4 Juli 2014
v
Universitas Indonesia
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Swt. yang melimpahkan segala
rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang
menjadi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister di Fakultas Hukum
Universitas Indonesia. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada
baginda nabi Muhammad S.A.W, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga
hari kiamat.
Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan tesis ini tidak lepas dari
peran berbagai pihak yang telah banyak memberikan bantuan, nasehat, bimbingan
dan dukungan. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih
yang tak terhingga khususnya kepada:
1. Kedua orangtuaku tercinta Hj. Siti Ma’rufah dan H. Mohammad Mathori
Choliq, kakakku tercinta Mashobihatul Lailiyah.
2. Ibu Farida Prihatini, S.H., M.H., CN. Sebagai pembimbing tesis yang telah
menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam
menyusun tesis ini.
3. Ibu Prof. Dr. Uswatun Hasanah selaku ketua peminatan Hukum Ekonomi
Islam, yang telah memberikan ilmunya bagi kami semua mahasiswa peminatan
Hukum Ekonomi Islam dan selalu mendorong kami semua untuk melanjutkan
perjuangan bliau.
4. Bapak dan Ibu Dosen peminatan Hukum Ekonomi Islam, Ibu Dr. Gemala
Dewi, S.H., LL.M., Ibu Dr. Yenni Salma Barlinti, S.H., M.H., Ibu Neng
Djubaedah, S.H., M.H., Ph.D., bapak Prof. Dr. Ahmad Sukarja, S.H., MA.,
bapak Prof. Dr. Hi. Fathurrahman Djamil, M.A., bapak Prof. Dr. Hi Rifyal
Ka’bah, M.A. (alm.), Bapak Dr. Yunus Husain, S.H., LL.M., ibu
Wirdyaningsih, S.H., M.H., bapak Dr. Miftahul Huda S.H., LL.M., bapak Dr.
Zulkarnaen Sitompul, S.H. LL.M., bapak Rifki Ismal, SE., MA., Ph.D. bapak
Heru Susetyo, S.H., LL.M, M.Si., Ph.D beserta seluruh stsf karyawan Fakultas
Hukum Univessitas Indonesia Program Pasca Sarjana yang telah memberikan
vi
Universitas Indonesia
ilmu pengetahuan dan pembelajaran berharga bagi penulis serta memberikan
kemudahan dan bantuannya selama ini
5. Seluruh kakak, teman-teman dan adik-adik mahasiswa Pasca Sarjana
Peminatan Hukum Ekonomi Islam semoga kalian selalu menjadi yang terbaik
dimanapun berada.
6. Sahabat dan Teman-teman satu perjuangan di kontrakan Utan Kayu -
Matraman, terimakasih atas kebersamaan selama ini, semoga kalian semua
sukses selalu, amiin.
7. Semua pihak yang mungkin belum saya sebutkan dan sahabat-sahabat yang
telah membantu penulis hingga terselesaikanya tesis ini, khususnya kepada
Gilang Cempaka yang selalu mengingatkan untuk makan dan tidur dan jaga
kesehatan setiap saat, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal
atas jasa dan bantuan yang telah diberikan. Amiin
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini banyak
kekurangannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang
dapat menyempurnakan penulisan ini sehingga dapat bermanfaat dan berguna
untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Amiin.
Jakarta, 4 Juli 2014.
Penulis
(Mohammad Aniq Kamaluddin)
vii
Universitas Indonesia
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di
bawah ini:
Nama : Mohammad Aniq Kamaluddin
NPM : 1206183905
Program Studi : Ilmu Hukum (Hukum Ekonomi Islam)
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Non-exclusive Royalti
Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:
“Peran Bank Syari’ah Dalam Pengelolaan Wakaf Uang”
Beserta perangkat yang ada (jika diperluka). Dengan Hak Bebas Royalti
Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media atau
memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan
mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya
sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.
Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.
Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 10 Januari 2014
Yang Menyatakan
(Mohammad Aniq Kamaluddin)
viii
Universitas Indonesia
ABSTRAK
Nama : Mohammad Aniq Kamaluddin
NPM :1206183905
Program Studi :Ilmu Hukum (Hukum Ekonomi Islam)
Judul :Peran Bank Syari’ah dalam Pengelolaan Wakaf
Uang
Wakaf dikenal umat muslim sebagai bentuk amal jariyah yang
memiliki peran penting dalam kesejahteraan masyarakat. Salah satu
bentuk wakaf yang akhir-akhir ini mulai banyak diperkenalkan adalah
wakaf uang. Praktik wakaf uang yang terjadi di Negara-Negara Islam
menggunakan bank syari’ah sebagai pengelola wakaf uang tersebut.
Begitupun di Indonesia telah lahir undang-undang wakaf yang
memperbolehkan wakaf benda bergerak berupa uang melalui lembaga
keuangan syari’ah yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Hal yang menjadi
pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Peran Bank
Syari’ah Dalam Pengelolaan Wakaf Uang. Dalam penulisan tesis ini
penulis menggunakan pendekatan kepustakaan, dimana hasil dari telaah
kepustakaan diambil dari buku-buku, majalah, karya ilmiah yang ada
kaitannya dengan perbankan syari’ah dan wakaf uang, kemudian penulis
analisis dengan pembahasan wakaf uang, kemudian penulis analisis
menggunakan metode deskriptif analitik dan konten analisis. Dalam
penelitian ini penulis temukan bahwa peran bank syari’ah sangat
diperlukan dalam pengelolaan wakaf uang karena prinsip wakaf yang dana
pokoknya tidak boleh berkurang sedikitpun membutuhkan peran pengelola
yang ahli dalam hal ini bank menjadi alternatif terbaik untuk mengelola
karena jaringan kantornya yang luas, memiliki pengalaman dalam
mengelola dana sosial, memiliki kredibelitas serta telah berhubungan
dengan lembaga penjamin simpanan.
Kata Kunci: Peran Bank Syari’ah, Dalam Pengelolaan Wakaf Uang.
ix
Universitas Indonesia
ABSTRACT
Name : Mohammad Aniq Kamaluddin
NPM :1206183905
Major Subject :Law (Islamic Economimic of Law)
Title : The Role Of Sharia Bank In Cash Waqf
Management
Endowments known to Muslims as a form of perpetual charity which has
an important role in the welfare of the community. One form of waqf lately lot of
is introduced is cash waqf. Cash waqf practice that occurs in Islamic Countries
using Shari'ah bank as manager of the cash waqf. Likewise in Indonesia has born
the law of waqf endowments that allow the moving objects in the form of money
through Shari'ah financial institution designated by the Minister of Religious
Affairs. Things that are to be issue in this study is how the role of the Sharia Bank
In management of cash waqf. In this thesis the writer uses literary approach,
where the results of the study of literature is taken from books, magazines,
scientific works related to the shariah banking and cash waqf and then the author
analyzes the discussion of cash waqf, then is analyzed using descriptive analytic
methods and content analysis. In this study the authors found that the role of
Sharia banks in management of cash waqf is very important, because the principle
of waqf that funds should not be reduced at all require skilled managers role. in
this case the bank's Shari'ah be the best alternative for managing because have
extensive office network, experience in managing social funds, credible and has
had good cooperation with the deposit insurance agency.
Keywords: Role of Sharia Bank, In the cash waqf, Management.
x
Universitas Indonesia
DAFTAR ISI
BAB 1 PENDAHULUAN............................................................................... 1 1.1. Latar Belakang............................................................................. 1 1.2. Pokok Masalah............................................................................. 5 1.3. Tujuan Penelitian.......................................................................... 5 1.4. Manfaat Penelitian........................................................................ 5 1.5 . Pembatasan Masalah..................................................................... 6 1.6 . Kegunaan Penelitian. ................................................................... 6 1.7 . Kerangka Konseptual.................................................................... 7 1.8. Kerangka Teori............................................................................. 10 1.9. Jenis Penelitian.............................................................................. 21 1.10. Pendekatan Masalah.................................................................... 21 1.11. Metode Penelitian....................................................................... 22 1.12. Tehnik Pengumpulan Data.......................................................... 25 1.13. Sistematika Penulisan................................................................. 25
BAB 2 TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF...................................... 27 2.1.Pengertian Wakaf........................................................................... 27 2.2.Dasar Hukum Wakaf...................................................................... 30 2.3.Fungsi dan Tujuan Wakaf.............................................................. 40 2.4.Rukun dan Syarat Wakaf............................................................... 41 2.5.Syarat Jangka Waktu Wakaf.......................................................... 49 2.6.Macam-macam Wakaf................................................................... 50 2.7.Status Harta Wakaf........................................................................ 52 2.8.Hakikat Harta Benda Wakaf.......................................................... 53 2.9.Wakaf dalam hukum Islam............................................................ 58
BAB 3 TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN SYARI’AH 62 3. 1. Sejarah Kelahiran Bank Islam..................................................... 62 3.1.1. Sejarah kelahiran Bank........................................................ 62 3.1.2. Sejarah Bank Pada Masa Rasulullah SAW.......................... 63 3.1.3. Munculnya Gagasan Bank Islam......................................... 64 3.2. Dasar hukum bank syari’ah........................................................... 68 3.2.1. Dasar hukum bank syari’ah di Indonesia............................ 76 3.2.2. Peraturan Hukum Terkait Dengan Bank Syariah di
Indonesia............................................................................ 76 3.2.3. Peraturan-peratran Terkait Hukum Positif Bank Umum
Syari’ah.............................................................................. 79 3.3. Pengertian Bank Syari’ah.............................................................. 80 3.4. Akad-Akad Yang Dipergunakan Dalam Perbankan
Syari’ah.......................................................................................... 89 1. Akad Mudharabah................................................................. 88 2. Akad Musyarakah.................................................................. 89 3. Akad Wadi’ah (Simpanan Murni) ........................................ 89 4. Akad At-Tijarah (Jual Beli) .................................................. 90 3.5. Rukun dan Syarat Dalam Perbankan Syari’ah.............................. 91 3.6. Prinsip Hukum Perbankan Syari’ah.............................................. 92
xi
Universitas Indonesia
3.7. Tujuan Perbankan syariah............................................................. 93 3.8. Ciri-Ciri bank Syari’ah dan perbedaanya dengan bank
konvensional.................................................................................. 99 3.8.1. Ciri-ciri bank syari’ah....................................................... 100 3.8.2. Perbandingan Antara Bank Syariah Dan Bank
Konvensional..................................................................... 99 3.9. Sistem Operasional Bank Syariah.............................................. 100 3.10. Sumber-Sumber Dana Bank Syariah.......................................... 101 3.11. Fungsi Bank Syari’ah................................................................. 102 3.12. Jenis - jenis Bank Syariah........................................................... 102
BAB 4 PERAN PERBANKAN SYARI’AH DALAM PENGELOLAAN
WAKAF UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NO.41
TAHUN 2004 TENTANG WAKAF................................................. 112 4.1. Dasar Hukum Wakaf Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2004 Tentang Wakaf...................................................................... 112 4.2. Peraturan Pengelolaan Wakaf Uang Oleh Bank Syariah
Menurut Undang-Undang Wakaf................................................... 118 4.3. Beberapa Akad Syari’ah Yang Digunakan Dalam Pengelolaan
Wakaf Uang Agar Dana Pokok Wakaf Tersebut Tidak
Berkurang....................................................................................... 123 4.3.1 Al-Mudharabah................................................................. 124 4.3.2 Al-Musyarakah................................................................. 126 4.3.3 Al-Murabahah................................................................... 127 4.3.4 Al-Ijarah ........................................................................... 128 4.4. Alternatif Peran Perbankan Syari’ah Dalam Pengelolaan Wakaf
Uang.............................................................................................. 129 4.4.1 Bank Syari’ah Sebagai Nazhir Penerima, Penyalur dan
Pengelola Dana Wakaf...................................................... 129
4.4.2 Bank Syari’ah Sebagai Nazhir Penerima dan Penyalur
Dana Wakaf...................................................................... 130 4.4.3 Bank Syari’ah Sebagai Pengelola Dana Wakaf............... 132 4.4.4 Bank Syari’ah Sebagai Kustodi........................................ 133 4.4.5 Bank Syari’ah sebagai Pelaksana Administrasi Wakaf
Uang.................................................................................. 135 4.5 Mekanisme Perlindungan Dana Wakaf Oleh Bank
Syariah........................................................................................ 137 4.5.1 Bentuk-Bentuk Perlindungan Nasabah Oleh Bank.......... 140 4.5.1.1 Perlindungan Tidak Langsung..................................... 141 4.5.1.2 Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principles)............. 141 4.5.1.3 Batas Maksimum Pemberian Kredit (“BMPK”).......... 143 4.5.1.4 Kewajiban Mengumumkan Neraca dan Perhitungan
Laba Rugi................................................................... 147 4.5.1.5 Mengadakan Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi
Bank............................................................................ 148 4.5.1.6 Melindungi Nasabah Berdasarkan Undang-Undang
Perlindungan Konsumen............................................... 148 4.6 Perlindungan Hukum Terhadap Dana Wakaf Melalui 149
xii
Universitas Indonesia
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)..................................... 4.6.1 Peranan LPS Dalam Melindungi Nasabah............................ 149 4.6.2 Pihak Yang Terlibat Dalam Lembaga Penjamin Simpanan.. 152 4.6.3 Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Lembaga Penjamin
Simpanan................................................................................ 156 4.7 Simpanan Yang Dijamin Oleh LPS.......................................... 160 4.8 Analisis Terhadap Peraturan-Peraturan Perbankan Syari’ah
Dalam Pengelolaan Wakaf Uang ............................................ 161
BAB 5 PENUTUP........................................................................................... 169 5. 1 Kesimpulan................................................................................... 169 5.2. Saran-saran.................................................................................... 170
DAFTAR PUSTAKA........................................................................................ 172
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Wakaf sudah dikenal sejak lama oleh semua peradaban manusia dan
biasanya wakaf diwujudkan dalam bentuk tempat peribadatan yang dikelola oleh
para pemuka agama.1 Hal ini diperkuat dengan pernyataan Imam Syafi‟i yang
menyatakan bahwa “wakaf merupakan ajaran umat Islam dan umat sebelumnya”.2
Wakaf mempunyai derajat khusus, karena manfaatnya sangat besar bagi
kemaslahatan umat. Maka suatu hal wajar apabila wakaf disamakan statusnya
dengan ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya.
Itulah keistimewaan wakaf, yang tidak dimiliki amal ibadah lain, sebagaimana
Rasulullah S.A.W bersabda:
اهلل عه أبى ريرة أن رسول اهلل صلى
إذا مات » قال -علي وسلم
اإلوسان اوقطع عى عمل إال مه
ثالثة إال مه صدقة جارية أو علم
لح يدعو ل يىتفع ب أو ولد صا
)رواي مسلم(«.Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah saw
bersabda: Apabila seseorang meninggal dunia maka terputuslah semua amalannya
kecuali tiga, yaitu: sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat atau anak
shalih yang mendo‟akan kepadanya.” (HR. Muslim)3
1 Mundir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, Jakarta: Khalifa, cet 1, 2000, hlm. 16.
2 Ibid,.
3 Ibid, hlm. 14.
1
Universitas Indonesia
Wakaf telah lama dikenal masyarakat muslim sebagai salah satu bentuk
amal jariyah yang berperan penting bagi pengembangan sosial, ekonomi dan
budaya dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu
bentuk wakaf yang akhir-akhir ini mulai banyak diperkenalkan adalah wakaf
uang. Wakaf uang sebagai salah satu alternatif atas pengentasan kemiskinan telah
diterapkan di beberapa Negara Islam. Terutama di Bangladesh4. Disana wakaf
telah dikelola oleh sebuah bank yang di kenal dengan nama (SIBL) Social
Investment Bank Limited. SIBL berperan sebagai nadzir wakaf uang yang
menerima, mengelola dan menyalurkan hasil dari investasi wakaf uang tersebut.
Sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang
tersebut dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan yang berbeda seperti
pemeliharaan harta-harta wakaf itu sendiri, membangun usaha-usaha yang lebih
produktif, memberikan beasiswa, dan lain-lain. Yang paling penting wakaf uang
di Bangladesh difungsikan sebagai penghapuskan kemiskinan serta
menanggulangi keterpurukan di bidang ekonomi, bidang pendidikan, riset dan
kesehatan.5
Adanya pergeseran bentuk harta/benda wakaf menjadi lebih sederhana
seperti uang telah berdampak luas. Pergeseran itu telah mengubah pandangan dan
kebiasaan lama, di mana sebelumnya kesempatan melakukan wakaf hanya dapat
melalui asset tetap berupa tanah dan/atau bangunan. Perubahan lain adalah
pandangan lama bahwa berwakaf harus bernilai besar menjadi sirna. Dengan
bentuk uang, wakaf dapat dilakukan dengan nilai kecil tertentu, yang tentunya
menjadi lebih dapat dilakukan oleh semua golongan. Adanya dukungan
pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
yang juga mengakomodir wakaf uang, telah membuka kesempatan masyarakat di
semua golongan (tidak hanya orang kaya) untuk dapat ikut serta berwakaf.
Salah satu ciri khas wakaf uang setelah disahkannya Undang-Undang
Wakaf No. 41 tahun 2004 adalah dibentuknya Lembaga Keuangan Syariah
4 M.A. Mannan; “Sertifikat Waqf Tunai, Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam”
CIBER bekerjasama dengan PKTTI-UI, hlm: 50-51
5 Ibid.
2
Universitas Indonesia
Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No.
92-96 Tahun 2008 dimana telah ditunjuk lima bank syariah sebagai LKS-PWU,
yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Nasional Indonesia
(BNI) Syari‟ah, Bank Mega Syari‟ah dan Bank DKI Syari‟ah dan sekarang telah
ada 11 (sebelas) LKS-PWU yang terakhir hingga penelitian tesis ini adalah Bank
Pembangunan Daerah Riau sebagai LKS-PWU berdasarkan Keputusan Menteri
Agama Rebublik Indonesia No.179 Tahun 2010. Keputusan Menteri Agama ini
sesuai dengan amanat UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terutama pasal 28.6
Di Indonesia hingga saat ini yang bertanggungjawab tentang pengelolaan
wakaf adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI), sebagaimana yang tercantum dalam
Peraturan Pemerintah No. 42 Pasal 48 ayat (1) dan ada beberapa Bank Syari‟ah
yang di tunjuk oleh Menteri sebagai Lembaga Keuangan Syari‟ah Penerima
Wakaf Uang (LKS-PWU). Dipilihnya beberapa bank syari‟ah sebagai penerima
wakaf uang tersebut memang telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 42
Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang
Wakaf, karena untk mengelola harta wakaf yang tidak boleh berkurang sedikitpun
itu diperlukan peran pihak-pihak yang ahli mengelola uang tersebut, sehingga
nadzir dalam hal ini BWI (badan Wakaf Indonesia) bekerja sama dengan beberapa
bank syari‟ah yang ditunjuk sebagai LKS-PWU untuk turut mengembangkan
harta wakaf tersebut, namaun perlu digaris bawahi bahwa LKS-PWU tersebut
hanya sebagai penitipan bukan pengelola. hal ini sebagaimana yang dimaksud
oleh Pasal 28 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dimana Wakif dapat
mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syari‟ah
yang di tunjuk oleh Menteri Agama.
Beberapa alasan dipilihnya bank syari‟ah sebagai LKS-PWU tersebut
adalah karena dipandang memiliki beberapa keunggulan, antara lain:7
6 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Pasal 28: Wakif dapat mewakafkan benda bergerak
berupa uang melalui lembaga keuangan syari‟ah yang ditunjuk oleh Menteri.
7 Ahmad Furqon “Praktik Wakaf Uang Di Bank Syari‟ah Mandiri” Jurnal IAIN Walisongo
Semarang, 2010,
3
Universitas Indonesia
1. Jaringan kantor cabang yang tersebar di seluruh Provinsi, Kabupaten
maupun Kota. Dengan relatif luasnya jaringan kantor perbankan
diharapkan akan lebih mengefektifkan sosialisasi wakaf uang kepada
masyarakat, sehingga penggalangan dana wakaf menjadi lebih optimal
dan juga membantu efektifitas dan efisiensi penyampaian dana wakaf
kepada al-mauquf alaih (penerima wakaf).
2. Lembaga perbankan merupakan lembaga yang memiliki pengalaman
dalam mengelola dana masyarakat dan juga berpengalaman sebagai
lembaga perantara. Dengan pengalaman tersebut, apabila bank syariah
diamanatkan untuk membantu memaksimalkan wakaf uang tentunya
hal itu akan bisa terwujud.
3. Pengalaman jaringan informasi dan peta distribusi sebagai pengelola
dana untuk disalurkan kepada pihak tertentu, lembaga perbankan
memiliki akses informasi yang cukup dan peta distribusi yang jelas
kemana dana-dana tersebut akan disalurkan. Dalam praktek
operasional selanjutnya, ketiga hal tersebut menjadi hal yang paling
perlu untuk dipertimbangkan dalam mengoptimalkan penbgelolaan
dana wakaf.8
4. Bank memiliki kredibilitas dimata masyarakat dan dikontrol dengan
perUndang-Undangan yang berlaku. Disamping itu bank Syariah
dipantau langsung oleh Dewan Pengawas Syari‟ah, sehingga dapat
lebih menjamin tentang ke-Syari‟ahan wakaf uang ini.
Tetapi berbagai keunggulan yang di miliki bank Syari‟ah sebagai LKS-
PWU tersebut ternyata belum mampu menjawab keinginan masyarakat dan tujuan
dari wakaf itu sendiri, antara lain penyebabnya adalah:
a. Status Bank Syariah LKS-PWU yang hanya sebagai “Bank Penerima”
bukan sebagai “Bank Pengelola” menjadikannya tidak terlalu aktif
dalam fundrising.dan karena yang paling merasa bertanggungjawab
terhadap fundrising tersebut adalah nadzir wakaf uang.
8 Mustofa Edwin & Uswatun Hasanah (ed), Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, Peluang
dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat, (Jakarta: PSTTI-IU, 2001), hlm.105-106
4
Universitas Indonesia
b. Status Bank Syariah LKS-PWU sebagai Unit bisnis yang bekerja
untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya, memandang program
wakaf uang bukanlah program yang akan mendatangkan banyak
keuntungan sehingga terkalahkan dengan produk lainnya yang lebih
mendatangkan banyak keuntungan.
c. Belum ada divisi khusus yang mengurus masalah wakaf uang di Bank
Syariah LKS-PWU.9
Oleh karena itu menurut hemat peneliti Indonesia sudah saatnya
memiliki “Bank Syari‟ah sendiri sebagai Nadzir wakaf Uang” seperti
negara Bangladesh yang mampu menjadi alternatif untuk mengentaskan
kemiskinan dan menanggulangi krisis. Karena pengelolaan wakaf uang
seperti didalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 menentukan bahwa
ada tiga pihak yang terkait dengan pengelolaan wakaf uang di Indonesia
yaitu LKS sebagai lembaga penghimpun dana, BWI sebagai pihak yang
melakukan pengelolaan dan pengembangan wakaf, dan nazhir sebagai
pengelola wakaf uang. Ternyata melalui mekanisme pengelolaan seperti
ini, potensi pengelolaan wakaf di Indonesia belum optimal, pengelolaan
dana wakaf yang dilakukan oleh banyak pihak mengakibatkan mekanisme
berwakaf dan pengembangannya menjadi lama dan rumit. LKS-PWU yang
statusnya hanya sebagai bank kustodi (penitipan), membuat keunggulan-
keunggulan yang dimilikinya belum berjalan secara maksimal karena
hanya sebagai tempat penitipan dan bukan sebagai pihak pengelola harta
wakaf.
Untuk mengoptimalkan wakaf uang tersebut, bank wakaf nantinya
diharuskan berhubungan dengan Lembaga Penjamin Syari‟ah agar dana
pokok wakaf tersebut tidak berkurang sedikitpun sebagaimana konsep
wakaf dalam hadis Rasulullah S.A.W. Namun untuk mewujudkan itu
semua tidak mudah, perlu adanya payung hukum dan kemauan keras
9 Ahmad Furqon, Praktik Wakaf Uang Di Bank Syari‟ah Mandiri, Jurnal IAIN Walisongo
Semarang, 2010,
5
Universitas Indonesia
(political will) dari pemerintah. Maka dari itu peneliti ingin merumuskan
pokok masalah dalam tesis ini sebagai berikut:
1.2. Pokok Masalah
Dari dasar pemikiran di atas maka dapat ditarik pokok masalah
sebagai berikut:
1. Bagaimanakah peran Bank Syari‟ah dalam pengelolaan wakaf di
Indonesia?
2. Bagaimana cara Bank Syari‟ah memilih akad syari‟ah untuk
menghindarkan berkurangnya jumlah dana pokok wakaf uang dan
dana tersebut tetap bermanfaat secara produktif?
3. Bagaimana cara Bank Syari‟ah dan Lembaga Penjamin Simpanan
menjamin keutuhan wakaf uang agar dana pokok wakaf uang tersebut
tidak berkurang sedikitpun?
1.3. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan pokok masalah diatas maka peneliti dalam tesis ini memiliki
tujuan sebagai berikut:
1. Mengetahi bagaimana peran Bank Syari‟ah sebagai nadzir wakaf uang
di Indonesia
2. Mengetahui akad apasaja yang dapat digunakan oleh Bank Syariah
dalam mengelola wakaf uang ini, sehingga dana pokok wakaf tidak
berkurang sedikitpun sesuai konsep wakaf dan dana wakaf tetap
berjalan produktif.
3. Mengetahui bagaimana mekanisme bank Syari‟ah dan Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS) menjamin keutuhan wakaf uang agar dana
pokok wakaf uang tersebut tidak berkurang sedikitpun
1.4. Manfaat Penelitian
6
Universitas Indonesia
Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, peneliti berharap
dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Peneliti ingin agar pembaca turut memahami peraturan-peraturan tentang
peran Bank Syariah dalam pengelolaan Wakaf Uang.
2. Dengan mengetahui peraturan tentang boleh atau tidaknya Bank Syariah
menjadi Nadzir Wakaf Uang di Indonesia, maka peneliti ingin turut
mensosialisasikan aturan tersebut kepada masyarakat luas.
3. Dengan mengetahui apa saja akad yang digunakan oleh Bank Syariah
dalam mengelola wakaf uang maka peneliti ingin memberikan sumbangsih
saran dan kritik kepada pelaksanaan wakaf uang tersebut sehingga betul-
betul seperti yang dikehendaki syari‟ah.
4. Ingin mengetahui bagaimana mekanisme perlindungan dana pokok wakaf
uang oleh Bank Syariah dan Lembaga Penjamin Simpanan.
1.5 Pembatasan Masalah
Wakaf mempunyai ruang lingkup yang sangat luas sehingga
penelitian ini perlu dibatasi dalam hal-hal yang berkaitan dengan prinsip
umum wakaf dalam al-Qur‟an, as-Sunnah, pendapat fuqoha, peraturan
perUndang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Berhubung peran bank
syari‟ah juga memiliki cakupan yang luas maka berkaitan dengan tesis ini
peneliti membatasi untuk peran bank syari‟ah sebagai pengelola wakaf
uang. Secara lebih rinci peneliti akan membahas mengenai peran
perbankan syariah sebagai pengelola wakaf uang di Indonesia
1.6 Kegunaan Penelitian
1. Dalam penelitian ini peneliti berharap hasil penelitian ini mampu
memberikan masukan bagi hukum Islam di Indonesia khususnya tentang
Hukum yang berkaitan dengan Pengelolaan Wakaf Uang.
2. Peneliti juga berharap agar penelitian ini dapat memberi informasi kepada
pembaca agar lebih memahami tentang peraturan serta praktik pengelolaan
wakaf uang di Indonesia.
7
Universitas Indonesia
1.7 Kerangka Konseptual
Secara bahasa wakaf berasal dari bahasa arab al-waqf bentuk masdar dari
kata waqafa-yaqifu-wakfan10
. Kata al-Waqf semakna dengan kata al-Habs
bentuk masdar dari kata habasa-yahbisu-habsan artinya menahan.11
Berbagai
pengertian wakaf diatas dapat disimpulkan bahwa al-Habs maupun al-Waqf
sama sama mengandung makna menahan, mencegah atau melarang dan diam.
Dikatakan menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan
semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. dengan kata yang
lebih sederhana dapat diartikan sebagai “ditahan pokoknya dan dimanfaatkan
hasilnya dijalan Allah S.W.T.12
Definisi lain yang lebih sederhana diberikan oleh Kompilasi Hukum Islam
(KHI), wakaf adalah perbuatan hukum seorang atau sekelompok orang atau
badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan
melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau
kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.13
dalam pasal 1 ayat
(1) Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan bahwa
wakaf adalah perbuatan hukm wakif untuk memisahkan dan atau
menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya
atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna
keperluan ibadah dan atau kesejahtraan umum menurut syari‟ah.14
10
A.W.Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Surabaya:Pustaka
Progressif, Cet.Ke-14, 1997, hlm, 1576.
11 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 3, Beirut: Daar Al-Fikr, t.th,hlm, 515
12 Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer, Yogyakarta: Cakrawala, 2006,
hlm.60.
13 Mahkamah Agung, Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat (1).
14 Indonesia Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1)
8
Universitas Indonesia
Substansi yang terkandung dalam ajaran wakaf adalah adanya semangat
penegakan keadilan sosial melalui pendarmaan harta untuk kepentingan umum
walaupun wakaf merupakan amal kebajikan yang bersifat anjuran, tetapi daya
dorong untuk menciptakan pemerataan kesejahtraan sangat tinggi. Prinsip
dasar wakaf yang bertujuan menciptakan keadilan sosial merupakan
implementasi dari sistem ekonomi yang mendorong dan mengakui hak milik
indifidu dan masyarakat secara seimbang.15
Asas kemanfaatan suatu benda menjadi landasan yang paling relevan
dengan keberadaan benda itu sendiri. Lebih-lebih ibadah wakaf menurut para
ulama dikatagorikan sebagai amal ibadah shadaqoh jariah yang memiliki
pahala yang erus mengalir walaaupun yang melakukan telah meninggal dunia.
Sebagai objek wakaf, harta benda yang diwakafkan tersebut dapat dipandang
sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:16
1. Benda harus memiliki nilai guna. Wakaf adalah mengambil manfaat benda
yang diwakafkan serta mengharap pahala atau keridhaan Allah SWT atas
perbuatan tersebut. Tidaksah mewakafkan benda yang tidak boleh diam bil
manfaatnya sepwrti mewakafkan benda-benda memabukkan dan benda-
benda haram lainnya.
2. Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik sempurna (al-mil
at-tam) dari orang yang mewakafkan ketika terjadi akad wakaf. oleh
karenanya jika seorang mewakafkan benda yang bukan ata belum menjadi
miliknya, walaupun nantinya akan menjadi miliknya maka hukumnya
tidak sah., seperti mewakafkan benda atau sejumlah uang yang masih
belum di-undi dalam arisan, mewakafkan tanah yang masih dalam
sengketa atau masih menjadi jaminan dalam akad jual beli.
3. Benda yang diwakafkan harus diketahui ketika terjadi akad wakaf.
penetapan benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlahnya atau
menyebutkan dengan nisbahnya terhadap benda. Wakaf yang tidak
15
Direktorat Pemberdayaan wakaf Dirjen bimas Islam; Paradigma Baru wakaf di
Indonesia, (jakarta: Departemen Agama, 2006), hlm.90.
16 Ibid.,hlm. 40-42
9
Universitas Indonesia
menyebutkan secara jelas terhadap harta yang akan diwakafkan maka tidak
sah hukumnya seperti mewakafkan sebagian tanah.
4. Benda tetap atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan. Para
fuqoha‟berbeda pendapat tentang bentuk harya yang dapat diwakafkan itu.
Ulama Hanafiah berpendapat bahwa wakaf tidak dapat dilaksanakan
kecuali benda yang akan diwakafkan itu adalah harta tidak bergerak.
Dalam mazhab Hanafi dikenal dengan kaidah: “ pada prinsipnya, yang sah
diwakafkan adalah benda tidak bergerak”. Sumber kaidah ini adalah asas
paling berpengaruh terhadap wakaf , yaitu ta‟bid (tahan lama).17
Menurut Ulama yang mengikuti mazhab Syafi‟i berpendapat bahwa
barang yang diwakafkan haruslah barang yang kekal manfaatnya, baik
barang tidak bergerak, barang bergerak maupun barang kongsi (milik
bersama).18
Bahkan Ulama Malikiyyah menambahkan bahwa mewakafkan
dari sesuatu yang bermanfaat adalah sah hukumnya.
Hukum wakaf adalah hukum nasional yang berasal dari hukum
Islam dengan dilandasi teori tajdi, yang menyatakan bahwa hukum Islam
bersifat dinamis, terhadapnya selalu diadakan tajdid atau pembaharuan.
Pembaharuan dalam hukum Islam dilakukan dengan melalui metode
ijtihad yaitu berusaha sungguh-sungguh untuk menemukan hukum.19
Salah satu pembaharuan wakaf adalah perubahan ruang lingkup
substansi yang diatur dalam Undang-Undang No. 41/2004 tentang wakaf.
dalam Undang-Undang ini objek wakaf tidak hanya terbatas pada wakaf
tanah milik, akan tetapi wakaf benda bergerak atau uang juga telah
diperbolehkan.
Menurut departemen Agama Rebublik Indonesia (2006) bahwa
Pengelolaan wakaf produktif tidak lepas dari peran Nadzir (pengelola
wakaf). dari segi ekonomi tanah yang sangat luas berpotensi secara
17
Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, Fiqh Wakaf (jakarta: Departemen
Agama, 2006), hlm.31
18 Ibid., hlm.32
19 Imam Suhadi, Wakaf Untuk Kesejahtraan Umat, cet-1 (Yogyakarta: PT. Dana Bakti
Prima Yasa, 2002), hlm.75.
10
Universitas Indonesia
produktif sudah sangat banyak. Banyak tanah wakaf dibangun menjadi
masjid atau musholla dan bila bila kita berfikir secara produktif, sisa tanah
itu dapat di bangun untuk apartemen, toko, kiyos, kontrakan dan lain
sebagainya untuk disewakan, kemudian hasil dari penyewaan tersebut
dapat dipergunakan untuk memelihara masjid atau musholla tersebut.
Sehingga tidak perlu sumbangan dari donatur. Atau misalnya ada tanah
yang letaknya sangat setrategis, tanah itu dapat di jadikan ruko atau hotel
yang kemudian hasilnya ditasyarufkan untuk mengentaskan kemiskinan.
Tetapi untuk mewujudkan itu semua tidak mudah, membutuhkan
modal besar, sehingga dengan adanya wakaf uang maka akan menjadi
solusi untuk memprouktifkan tanah-tanah yang masih belum produktif
tersebut.
Undang-unbdang tentang wakaf uang lahir dilatarbelakangi adanya
gagasan wakaf uang tunai oleh Prof. M.A. Manan seorang Ekonom asal
Bangladesh. Bermula dari gagasan tersebut, kemudian Direktorat
pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Rebublik Indonesia
mengirimkan surat permohonan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI)
untuk mengeluarkan fatwa wakaf uang. Sehingga keluarlah fatwa MUI
tentang wakaf uang yang hukumnya jawaz (boleh). Wakaf uang sangat
berperan dalam masyarakat jika nadzir mampu mengelola dengan
maksimal.
Dengan demikian agar uang hasil wakaf dapat berfungsi secara
produktif harus di kelola oleh orang yang betul-betul ahli, dalam hal ini
Bank syari‟ah adalah salah satu alternatif untuk mengelola wakaf uang
tersebut.
1.8. Kerangka Teori
Keadilan sosial adalah realitas sosial dimana setiap anggotanya memiliki
kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup pada
kemampuan aslinya.20
Dalam pengertian seperti itu, keadilan sosial sangat
ditekankan oleh al-Qur‟an. Dalam al-Qur‟an, keadilan yang terkait dengan makna
20 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 8
11
Universitas Indonesia
keadilan sosial seperti di atas, paling tidak, ada tiga: dalam pengertian persamaan
sosial seperti persamaan di depan hukum, keseimbangan atau tidak adanya
ketimpangan sebagai asas alam dan sosial dan tidak adanya kezaliman sosial
(proporsional dan memberikan hak kepada pemiliknya). Dalam al-Qur‟an
dijelaskan pula bahwa keadilan, termasuk di dalamnya keadilan sosial, akan
membawa pada ketaqwaan, sementara ketaqwaan akan membawa pada
kemakmuran. Sebaliknya, ketidakadilan, termasuk di dalamnya ketidakadilan
sosial akan membawa pada kesesatan dan akan menjauhkan dari rahmat Tuhan.21
Siring dengan penekanan al-Qur‟an pada keadilan sosial di atas, secara
teoritis, dalam konteks filantropi Islam zakat, infak, sedekah dan wakaf,
kelembagaan ini meskipun bagian dari ibadah ritual kegamaan yang langsung
berhubungan dengan Tuhan, tetapi juga memiliki fungsi sosial atau bertujuan
untuk menciptakan keadilan sosial, minimal keadilan distribusi ekonomi.22
Walaupun demikian cara yang dibenarkan Islam adalah bukan cara yang
ditempuh sosialisme komunisme yang represif yang meniscayakan adanya
diktator proletariat yang totaliter, yaitu kediktatoran atas nama tujuan
menciptakan suasana ekonomi sama rata sama rasa bagi kaum tertindas. Model ini
di dunia Arab ditempuh Jamal Abd an-Nashir di Mesir pada tahun 1950-1960-an,
dengan menasionalisasi seluruh harta kekayaan wakaf.23
Menurut prespektif Islam dalam mewujudkan wakaf untuk keadilan sosial
harus diimbangi dengan prinsip sosial yang lebih sesuai dengan cara-cara
demokratis. Cara ini hampir serupa dengan model sosialisme revisionis Eduard
Bernstein (1850-1932) dan kaum Fabianisme di Inggris (1884) yang percaya pada
upaya mewujudkan keadilan sosial secara rasional dan empiris serta pembaruan
yang perlahan-lahan, tanpa kekerasan yang menyertainya.24
21
M. Quraish Shihab, Wawasan Alquran, Bandung: Mizan, 1996, hlm. 110-117 dan Majid
Fachry, Etika dalam Islam, Terjemahan oleh Zakiyuddin Baidhawi dari Ethical Theories in
Islam, Yogyakarata: Pustaka Pelajar, 1996, hlm. 5-9.
22 http://bwi.or.id/index.php/ar/artikel/746-wakaf-untuk-keadilan-sosial-antara-teori-dan-
praktik , Wakaf Untuk Keadilan Sosial Antara Teori dan Praktik, diakses tanggal 6 juli 2014.
23 Ian Adam, Ideologi Politik Mutakhir, Konsep, Ragam, Kritik, dan Masa Depanya,
Terjemahan dari Political Ideology Today, Yogyakarta: Qalam, 2004, hlm. 190-192.
24 Ibid
12
Universitas Indonesia
Dalam bahasa politik Islam, keadilan sosial yang dikehendaki adalah
keadilan sosial yang diwujudkan dengan mempertimbangkan
prinsip syûra (melibatkan masyarakat/publik melalui dialog secara damai, bukan
dengan kekerasan), ijmâ‟ (konsensus, paling tidak bersama elite),
amânah (akuntabilitas, tidak adanya penyelewengan jabatan),
musâwah (persamaan antar manusia), al-„Adalah (keadilan, termasuk di dalamnya
keadilan politik (kekuasaan yang tidak terkonsentrasi pada kaum-kaum tertentu
saja), bai‟at (persetujuan dari perwakilan para elit dan/atau rakyat), dan amar
ma‟ruf nahyi munkar (konsep check and balance/kontrol terhadap pemerintah).
Tentu saja, prinsip-prinsip di atas, juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip
penegakkan hukum.25
Selain caranya yang tidak represif, yang dikehedaki Islam juga bukan
persamaan absolut seperti sosialisme komunisme, yaitu masyarakat sama rata
sama rasa dengan tidak mengakui kepemilikan individual dan tidak
mengakui human interest untuk memperoleh keuntungan. Sehingga berkaitan
dengan tulisan ini peneliti menggunakan konsep keadilan sosial menurut Sayyed
kutub dan John Rawl yang mana menurut Sayyed Qutub, keadilan sosial dalam
Islam mempunyai karakter khusus, yaitu kesatuan yang harmoni. Islam
memandang manusia sebagai kesatuan harmoni dan sebagai bagian dari harmoni
yang lebih luas dari alam raya di bawah arahan Penciptanya. Keadilan Islam
menyeimbangkan kapasitas dan keterbatasan manusia, individu dan kelompok,
masalah ekonomi dan spiritual dan variasi-variasi dalam kemampuan individu. Ia
berpihak pada kesamaan kesempatan dan mendorong kompetisi. Ia menjamin
kehidupan minimum bagi setiap orang dan menentang kemewahan, tetapi tidak
mengharapkan kesamaan kekayaan. OLeh karena itulah, menurut Islam keadalian
tidak harus sama tanpa ada perbedaan. Keadilan yang mutlak pasti membutuhkan
perbedaan, tetapi memberi kesempatan yang merata dan luas kepada mayarakat
untuk menjalani kehidupan. Tetapi tidak keluar dari prinsip-prinsip keagamaan
(Islam). Islam tidak menginginkan semua orang memilki jumlah kekayaan yang
sama dalam hal ekonomi. Karena hal itu sangat tidak mungkin terjadi. Tetapi
25
http://www.bwi.or.id/index.php/in/profil/divisi/litbang/27?start=28, Sukron Kamil,
“Wakaf Untuk Keadilan Sosial: Antara Teori dan Praktik” Artikel diakses tanggal 6 juli 2014.
13
Universitas Indonesia
Islam tidak menghalakan segala kemewahan yang mendorong manusia hanya
tertuju pada khidupan materi (dunia), tunduk pada nafsu syahwatnya, dan
menciptakan kelas-kelas yang berbeda dalam masyarakat.26
Konsep keadilan Sosial Barat Yang lebih dekat dengan Islam adalah konsep
keadilan sosial yang digagas John Rawls, yaitu keadilan sosial yang
mementingkan distribusi kekuasaan dan kekayaan yang sama, tetapi juga
mentoleransi distribusi yang berbeda bagi yang berbakat.27
Jika wakaf menjadi bagian dari lembaga keadilan sosial, maka lembaga
wakaf harus berfungsi juga sebagai civil society, yaitu masyarakat yang menjadi
prisai dalam berhadapan dengan negara yang cenderung hegomonik, dan jika
tidak hegomonik, mereka sebagai mitra dan berperan melengkapi kebutuhan
sosial.28
Hal ini mengingat sumber ketidakadilan sosial seringkali adalah hal-hal
struktural. Karenanya, ketidakadilan sosial sering disebut sebagai ketidakadilan
struktural.
Guna melahirkan keadilan sosial lewat wakaf, maka dalam fikih, baik klasik
maupun modern, nazhir wakaf dibolehkan melakukan penukaran benda wakaf
seperti dijual lalu hasilnya disatukan dengan harta wakaf lainnya sebagaimana
yang terjadi di Libya dan Mesir.29
Negara Indonesia adalah salah satu dari negara yang struktur ekonominya
terjadi ketimpangan, karena masih dikuasai oleh orang-orang tertentu saja. Seperti
data yang diperlihatkan Tempo, Rabu, 12 Maret 2014 dari survey yang dilakukan
oleh FORBES, bahwa 19 orang Indonesia masuk jajaran orang terkaya di dunia.
26
http://insistnet.com/teori-keadilan-sosial-sayyid-qutb/, Teori Keadilan Sosial Sayyid
Qutb, diakses tanggal 6 juli 2014.
27 Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern I, Terjemahan oleh Robert MZL
dari Sosiological Theory Clasical Founder and Contemporery Perspectives (1981), Jakarta:
Gramedia, 1994, hlm. 154-161, Ian Adam, Ideologi Politik Mutakhir,Adam, 2004, hlm. 68, 190-
199, dan Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, 1995, hlm. 83
28 Hendro Parasetyo, Ali Munhanif, dkk., Islam dan Civil Society Pandangan Muslim
Indonesia, Jakarta: Gramedia dan PPIM, hlm. 8-9 dan lihat juga Adam Kuper dan Jessica
Kuper, Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial, Jilid I, Jakarta Rajawali Pers, 2000, hlm. 113-115
29 Abd al-Jalil „Abd ar-Rahman „Asyub, Kitâb al-Waqf, hlm. 19-20, Muhammad Abu
Zahrah, Muhâdarât Fî al-Waqf, Kairo: Dar al-Fikr, 2004, hlm. 159-163, Dirjen Bimas Islam dan
Haji Depag RI, Pedoman. hlm. 77, dan ad-Dimyathi, I‟ânah at-Thâlibin, Jilid III, Bandung: al-
Ma‟arif, Tthlm., hlm. 179
14
Universitas Indonesia
Mereka setara dengan PDB Indonesia. Bersamaan dengan hal tersebut
berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan RI dan
Badan Pusat Statistik pada tahun 2013 indeks Gini Indonesia kurang lebih 0,41 –
0,42. Jumlah penduduk miskin Indonesia pada bulan Maret 2013 adalah 28,07 juta
jiwa dan pada sebtember 2013 meningkat menjadi 28,55 juta jiwa artinya masih
sekitar 11,47% dari jumlah penduduk Indonesia itu adalah golongan orang miskin.
Saat ini ketimpangan tersebut dapat kita lihat di sekeliling kita, masyarakat
dengan modal kecil harus tersingkir dengan adanya pengusaha-pengusaha yang
ber modal besar. Seperti mini market yang bebas berdiri dimana-mana sementara
pedagang kecil dan kaki lima senantiasa di gusur dan tidak mendapat tempat lagi
untuk menggerakkan perekonomiannya itu. Sehingga kantong-kantong finansial
hanya terfokus pada satu titik saja, yaitu mereka yang ber modal besar.
Penderitaan masyarakat miskin tersebut lebih memprihatinkan lagi
manakala harga-harga kebutuhan pokok rumah tangga terus merangkak naik
sedangkan penghasilan yang diterima semakin memprihatinkan. Mereka yang
bekerja sebagai buruh, upah yang mereka terima dari tempat kerjannya tidak
mencukupi untuk menunjang kebutuhan mereka sehari-hari. Itu semua
mengakibtkan tingkat kriminalitas terus naik dari tahun ketahun, yakni sekitar
13.7% per tahun yang sebagian besar disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang
mendesak.30
Untuk meminimalisir kesenjangan masyarakat kita itu dibutuhkan sebuah
gagasan cemerlang, diantaranya memaksimalkan konsep-konsep kesejahteraan
dan keadilan sosial yang telah ditawarkan agama Islam diantaranya pengelolaan
wakaf uang.
Secara teoritik, dalam Islam, tujuan diberlakukannya wakaf bisa dipastikan
adalah untuk merealisasikan keadilan sosial, minimal keadilan ekonomi,
kesehatan, dan pendidikan. Hal ini karena peran wakaf lebih dominan dibanding
zakat dan sedekah lainnya. Selain sebagai tolak ukur keimanan seorang hamba,
wakaf juga merupakan institusi distribusi kekayaan agar terjadi pemerataan
ekonomi dan juga merupakan simbol dari sistem ekonomi yang dikehendaki
30
http://www.intellitrac.co.id/statistik-kriminalitas-Indonesia-2013/, Statistik Kriminalitas
Indonesia 2013, diakses pada 6 Juli 2014.
15
Universitas Indonesia
Islam, yaitu hak-hak Individu diakui tetapi hak-hak sosial tetap diutamakan.
Lewat wakaf dan ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) diharapkan proses konsentrasi
kekayaan tidak terjadi, tetapi justru selalu terurai tercipta sirkulasi atau peredaran
surplus kekayaan di kalangan semua masyarakat sebagai tujuan utama ekonomi
yang sehat.31
Dalam Alqur‟an, tujuan distribusi ekonomi itu antara lain terlihat dalam al-
Qur‟an Surat Adz-Dzariyat: 19
Artinya: Pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta
dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.32
yang dimaksud dengan orang miskin yang tidak mendapat bagian diatas
ialah orang miskin yang tidak meminta-minta.
Kemudian didalam al-Qur‟an Surat Al-Ma‟arij 24-25:
Artinya: Orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi
orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang
tidak mau meminta).33
“Dalam kekayaan mereka (orang-orang kaya) terdapat hak bagi para
peminta-minta dan yang terhalang (ekonominya)”. Tujuannya adalah agar terjadi
perputaran kekayaan.
Kemudian didalam al-Qur‟an Surat Al-Hasyr 59:7
31
Ismail Raj‟i Al-Faruqi dan Lois Lamya Al-Faruqi, Atlas Budaya Islam, Menjelajah
Peradaban Gemilang, Bandung: Mizan, 1998, hlm. 179-181 dan Abdul Manan, Teori dan
Praktek Ejkonomi Islam, Terjemahan dari Islamic Economics, Theory and Practice oleh M.
Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf,199, hlm. 232
32 Al-Qur‟an dan Terjemahnya, Mujamma‟ al Khadim al Haramain asy Syarifain al Malik
Fadhli Thiba‟at al Mushhaf asy Syarif, Madinah al Munawwarah, 1411 H., hlm. 859.
33 Ibid.,973.
16
Universitas Indonesia
Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya
(dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah,
untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang
yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang
Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah.
dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada
Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.34
Dimana ayat ini diperkuat oleh al-Qur‟an Surat at-Taubah 9:60.
Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-
orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk
(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk
mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan
Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. 35
Dalam ayat yang disebut terakhir, filantropi36
Islam, baik yang wajib
maupun yang sunnah seperti wakaf, ditujukan untuk menangulangi kemiskinan,
karena penerima prioritasnya adalah kelompok fakir dan miskin.
Dalam hal ini, Islam memandang:
34 Ibid.,hlm. 974.
35 Ibid, hlm. 288.
36 Filantropi adalah cinta kasih terhadap sesama manusia.
17
Universitas Indonesia
1. Bahwa akumulasi kekayaan seseorang dibangun di atas keringat orang-orang
miskin, karena di dunia ini tidak ada seorangpun yang kaya yang bisa
beraktifitas tanpa orang-orang yang ekonominya lemah. Dalam kenyataannya,
orang-orang miskin memang sudah diberi upah atas kerjanya. Namun, jumlah
keuntungan yang didapat para majikan jauh lebih berlipat ganda dibandingkan
para buruhnya yang hanya didasarkan pada Upah Minimun Povinsi
(UMP) dan sejenisnya. Oleh karena itu, wakaf dan filantropi Islam lainnya
adalah bentuk ucapan terima kasih dan kerjasama kalangan kaya dan miskin.
2. Kesenjangan ekonomi akan mengakibatkan hancurnya sendi-sendi tatanan
sosial dan peradaban. Karena itu, menurut Nurcholish Madjid, berdasarkan
surat al-Humazah, Islam memandang kejahatan terbesar setelah syirik adalah
penumpukan kekayaan yang penggunaannya yang tidak benar.37
Menurut Ismail al-Faruqi dan Lois Lamya al-Faruqi, zakat dan sedekah
lainnya seperti wakaf harus mendorong investasi pendapatan dalam usaha
produktif yang akan menambah kekayaan masyarakat dan menciptakan
pekerjaan.38
Wakaf untuk keadilan sosial juga terdapat dalam Peraturan Perundangan
yang ada di Indonesia yang diambil dari ajaran Islam, yaitu Pasal 5 Undang-
Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 “Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan
manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk
memajukan kesejahteraan umum”.39
Dalam peraturan perundangan sebelumnya,
yaitu Pasal 216 Buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 2 PP. No. 28
/1977, juga disebutkan hal yang hampir sama, meskipun tujuan keadilan sosial,
tetapi tujan ekonominya kurang tampak “Fungsi wakaf adalah untuk mengekalkan
manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf”.
Fungsi wakaf dalam UU wakaf 2004 tersebut dapat dipahami sebagaimana
tercantum dalam penjelasannya, bahwa salah satu yang melatarbelakangi
37
Nurcholish Madjid, “Nilai Identitas Kader” dalam Pedoman LK I, Ciputat: HMI Ciputat,
1993
38 Ismail Raj‟i Al-Faruqi dan Lois Lamya Al-Faruqi, Atlas Budaya Islam, hlm. 179-181.
39 Departemen Agama RI, UU Wakaf No. 41 2004, Jakarta: Depag RI, 2004, hal. 3, 5.
18
Universitas Indonesia
kemunculan UU tersebut adalah realitas bahwa wakaf bukan yang menjadi pokok
kekuatan ekonomi Ummat Islam.40
Fungsi wakaf untuk keadilan sosial Islam sebagai mauqûf
„alaih (peruntukan wakaf) itu diperjelas lagi peruntukanya dalam dalam Pasal 22
Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam pasal tersebut
bahwa mauqûf „alaih (peruntukan) wakaf selain sarana kegiatan ibadah, juga
pendidikan, kesehatan, bantuan untuk fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu,
beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi Ummat, dan kemajuan
kesejahteraan umum lainnya.41
Selain untuk kepentingan keadilan ekonomi, jika wakaf sebagai lembaga
keadilan sosial, maka wakaf pun bisa difungsikan sebagai lembaga keadilan
politik, karena keadilan politik adalah sesuatu yang dianjurkan Islam. Misalnya
untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat yang terabaikan, meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik, mensosialisasikan
hak-hak warga, melakukan pendampingan masyarakat yang terpinggirkan,
pendidikan untuk keadilan bagi perempuan, dan mengembangkan kerukunan antar
umat beragama. Hal ini karena, menurut Kuntowijoyo, people power menjelang
Revolusi Islam Iran 1979 yang dipimpin para ulama terjadi, antara lain karena
para ulama memiliki sumber-sumber finansial yang independen dan kuat dari
zakat42
dan terutama dari wakaf yang terkait dengan masjid dan lembaga
pendidikan.
Di samping penjelasan di atas, wakaf untuk keadilan sosial Islam bisa dilihat
dari definisi wakaf dalam fikih dan asal usulnya. Wakaf secara ringkas
didefinisikan dengan: “menahan kapital yang mungkin diambil manfaatnya tanpa
menghabiskan atau merusak bendanya („ainnya) dan digunakan untuk kebaikan.43
40
“PP No. 28/1977 tentang Perwakafan Tanah Milik”, dalam HLM. Abdul Mannan dan M
Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama, Jakarta: Rajawali Pres, 2002,
hal. 395 “Buku III Kompilasi Hukum Islam Indonesia”, dalam Abdurrahman, Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992 hlm. 166.
41 Departemen Agama RI, UU Wakaf. hlm. 14
42 Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam, Bandung: Mizan, 1997, hlm. 130
43 Muhammad Ibn. Isma‟il as-San‟any, Subul as-Salam, (Mesir: Muhammad Ali Sabih, t.t)
Juz III, hlm.114.
19
Universitas Indonesia
Definisi ini berasal dari hadis Nabi Riwayat Bukhari dan Muslim bahwa ketika
Umar bin Khattab bercerita kepada Nabi Muhammad mengenai sebidang tanah
miliknya di Khaibar, lalu Nabi bersabda: “Jika engkau mau, tahan pokok
(kapital)-nya dan sedekahkan hasilnya”.44
Anjuran Nabi ini meskipun lebih
sebagai penjelasan atas pernyataan al-Qur‟an yang mendorong sangat kuat untuk
melakukan sedekah sebagai amal shaleh, tetapi juga terkait dengan lembaga yang
pernah berlaku pada suku pra Islam yang disebut himâ, yaitu sebidang lahan yang
disisihkan oleh suatu suku sebagai harta masyarakat untuk menggembalakan
ternak dan sebagainya, yang tidak bisa diklaim baik oleh individu maupun
keluarga manapun. Dalam hal ini, wakaf berawal dari praktik hima sebagai faktor
produksi bersama yang tujuannya adalah untuk perwujudan keadilan ekonomi.45
Praktik wakaf juga didasarkan pada hadis Riwayat Imam Muslim, dimana
wakaf merupakan sebuah upaya pengabadian amal tentu saja yang bersifat relatif
yang akan terus mengalir meskipun pelakunya telah meninggal dunia, melalui
pemanfaatan benda yang diwakafkan oleh publik untuk kemaslahatannya. Dengan
begitu, diharapkan pahalanya tetap mengalir kepada para pewakaf (wakif). Dalam
hadis tersebut, sebagai tindakan yang tidak teputus pahalanya, yaitu sedekah
jariah (wakaf) yang kedudukannya seimbang dengan ilmu yang bermanfaat dan
anak saleh yang mendo‟akan kedua orang tuanya.46
Mengingat wakaf sebagai institusi keadilan sosial Islam, berarti tidak ada
orang yang dikecualikan dalam pemanfaatannya, termasuk nonmuslim. meskipun
dalam masalah ini ulama Syafi‟iyah dalam permasalahan zakat berpendapat tidak
sahnya zakat jika diserahkan kepada fakir miskin yang non-Muslim, sekalipun
diperintahkan penguasa,47
tetapi berbeda sekali dalam soal wakaf. Fikih
Syafi‟iyah membolehkanya. Imam an-Nawawi dalam kitab ar-Raudhah, sebuah
44
Mundir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, Jakarta: Khalifa, cet 1, 2000, hlm. 16
45 Sayyid Sâbiq, Fiqh al-Sunnah, jilid III, Kairo: Dâr al-Tsaqafah al-Islâmiyyah, 1365
HLM. hlm. 259-261 dan Ibn Hajar al-„Asqalani, Bulûgh al-Marâm, Bandung: al-Ma‟arif, Tthlm.,
hlm. 191
46 Ibid
47 Syaikh Zainuddin Abd Al-Aziz Al-Malibari, Fath al-Mu‟în bi Syarh Qurrah al-
„Ain, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, Tthlm. hlm. 53.
20
Universitas Indonesia
buku yang terkenal tetapi kurang dijadikan rujukan di pesantren tradisional,
menjelaskan mengenai sahnya wakaf kepada nonmuslim (kafir dzimmî), baik dari
seorang Muslim maupun dari sesama nonmuslim dzimmî. Namun,
menurutnya, syaratnya adalah: (1). Benda yang diwakafkannya tidak
mengandung dan tidak diperuntukkan untuk kemaksiatan seperti tikar untuk
gereja dan lain-lain. (2). Benda wakafnya boleh dimiliki non Muslim tidak boleh
diwakafkan bila berupa al-Qur‟an dan budak Islam. walaupun alasan kedua ini
masih diperdebatkan. Demikian juga dengan buku fikih modern seperti Fiqh as-
Sunnah Sayyid Sabiq yang juga membolehkan pemberian wakaf kepada
nonmuslim dzimmî seperti kepada kaum Kristiani. Alasan yang dikemukan Sabiq
adalah karena telah dipraktikan Shofiyyah, istri Nabi, yang mewakafkan hartanya
kepada saudaranya yang Yahudi.48
Selain boleh digunakan untuk kepentingan ibadah (pembangunan masjid),
lembaga pendidikan dan para gurunya, pembangunan hotel atau pemondokan
untuk para musafir, juga kebutuhan minum, pengurusan mayat seperti pembelian
kain kafan, pembangunan dan rehabilitas jembatan, untuk para penghuni
penjara, rumah sakit, perpustakan, dan lainnya. Bahkan, berbeda dengan sedekah
lainnya, sebagian wakaf atau manfaatnya pun, seperti buku dan al-Qur‟an, boleh
didistribusikan atau dimanfaatkan oleh orang kaya yang tidak berhak menerima
zakat.49
Berdasarkan penjelasan di atas, dasar dari pendistribusian hasil wakaf
adalah istihsân (hal-hal yang dipandang baik) atau alasan
kemaslahatan (istishlah) yang dibenarkan oleh hadis riwayat Abdullah bin
Mas‟ud. Dalam hadis itu dijelaskan bahwa apa yang dipandang baik oleh kaum
muslimin, maka menurut Allah pun baik. Karena itu, dalam pendistribusian hasil
48
An-Nawawi, al-Raudhah, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt. Jilid IV,
hlm.381 sebagaimana dikutip Anwar Ibrahim, “Wakaf dalam Syari‟at Islam”, Makalah Workshop
Internasional Pemberdayaan Ekonomi Ummat melalui Pengelalolaan Wakaf Produktif, Batam:
Wisma Haji Batam, 7-8 Januari 2002, hlm. 16-17, Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Depag
RI, Fiqh Wakaf, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Depag RI, 2003, 47-48, dan Sayyid
Sabiq, Fiqh al-Sunnah, hlm. 263.
49 Abu Bakar Ahmad bin „Umar as-Syaibani, Kitâb Ahkâm al-Auqâf, Kairo: Maktabah as-
Tsaqafah ad-Diniyyah, Tthlm., hlm.294-295, „Abd al-Jalil „Abd ar-Rahman „Asyub, Kitâb al-
Waqf, Kairo: al-Afaq al-Arabiyyah, 2000, hlm. 31.
21
Universitas Indonesia
wakaf, seorang nâzhir wakaf bisa merujuk pada alasan untuk mendatangkan
kemaslahatan dan menolak kerusakan. Kemaslahatan yang disebut oleh as-
Syathibi (730-790 H) sebagai dharuriyyat (mendesak), baik untuk
menjaga agama (hifzh al-dîn), nyawa (hifzh al-nafs), kebebasan berpikir (hifzh al-
„aql), reproduksi (hifzh al-nasl) dan hak-hak ekonomi (hifzh al-mâl). Menurut as-
Syathibi, kemasalahatan merupakan inti syari‟ah Islam, dalil universal. Bahkan,
menurut al-‟Iz bin „Abd as-Salam, seluruh hukum Islam sesungguhnya adalah
untuk kemaslahatan manusia. As-Syathibi pun berpendapat juga bahwa jika
terjadi perbedaan antara dalil naqli (al-Qur‟an dan hadis) dengan kemaslahatan,
maka keduanya harus harus dikompromikan. Jadi, batasan sejauh mana hasil
wakaf khairî boleh didistribusikan adalah sejauh kemaslahatan menghendakinya.
1.9. Jenis Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang
menjabarkan fakta-fakta yang diperoleh sebagaimana adanya dan dianalisis
dengan teori keadilan sosial.50
Deskriptif analitis berarti bahwa penelitian ini
menggambarkan suatu peraturan hukum dalam konteks teori-teori hukum wakaf
uang dan pelaksanaannya di Indonesia serta menganalisis peran perbankan syariah
dalam mengelola wakaf uang.
1.10. Pendekatan Masalah
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan perUndang-Undangan (statutery approach) dan pendekatan
konseptual (conseptual approach). Pendekatan perUndang-Undangan digunakan
karena peneliti akan melakukan penelitian dengan menelaah semua Undang-
Undang dan regulasi yang terkait dengan peran Bank Syariah dalam pengelolaan
wakaf uang, serta asas-asas keadilan sosial yang mendasari dianjurkannya
perbankan syari‟ah menjadi nadzir wakaf dalam pengelolaan wakaf uang di
Indonesia.
50
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta 1986, hlm.10
22
Universitas Indonesia
1.11. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat hukum
normatif yang dimaksudkan untuk memberikan data mengenai peran bank
syari‟ah dalam pengelolaan wakaf uang. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi
permasalahan yang ada disekitar wakaf uang. Serta melakukan penilaian terhadap
perangkat hukum positif yang mengatur tentang peran perbankan syari‟ah dalam
mengelola wakaf uang.51
Penelitian ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum Islam yang
digunakan dalam hukum nasional yang mengatur tentang wakaf uang dan peran
perbankan syari‟ah yang diatur dalam Undang-Undang Nmor 41 Tahun 2004.52
Serta mencakup pula sejarah wakaf Islam. Dilihat dari disiplin ilmu yang
digunakan dalam penelitian ini, menambahkan data primer melalui metode
berupa wawancara. Melalui metode tersebut, data skunder atau penelitian
diperoleh dari sumber-sumber berupa bahan-bahan kepustakaan, yaitu antara
lain:53
1. Bahan Kepustakaan Primer yang terdiri dari
a. Kaedah hukum dasar, yaitu kaedah-kaedah hukum yang termuat dalam al-
Qur‟an dan Sunnah-sunnah Rasulallah SAW yang terkandung dalam
Hadits-hadits mengenai wakaf;
b. Peraturan perUndang-Undangan, yaitu:
1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
2) UU No.10 Tahun 1998
3) Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan
Kompilasi Hukum Islam;
51 Disadur dari Soerjono Suekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Satu
Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 10.
52 Ibid., 17
53 Ibid., 13
23
Universitas Indonesia
4) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia;
5) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009
6) Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi
Pendaftaran Wakaf Uang;
7) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang
Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
Bergerak Berupa Uang;
8) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang
Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nazhir Badan Wakaf
Indonesia;
9) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata
Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang;
10) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang
Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.
c. Bahan hukum tertulis lainnya, yaitu:
1) Penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;
2) Peraturan pemerintah Rebublik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang
Wakaf
3) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/Kep/Dir Tahun
1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
4) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/36/Kep/Dir Tahun
1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.
5) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Fatwa Tentang Wakaf Uang, 11 Mei
2002.
2. Bahan Kepustakaan Skunder: yaitu bahan hukum yang terdiri dari
literatur-literatur yang memuat data yang diperlukan bagi penelitian baik
dalam bentuk:
a. Rancangan perUndang-Undangan, yaitu:
24
Universitas Indonesia
1) Surat Presiden Rebublik Indonesia Nomor R.16/PUVII/2014
tentang RUU tentang Wakaf;
2) Penjelasan Pemerintah Mengenai Rancangan Undang-Undang
Rebublik Indonesia Tentang Wakaf;
3) Revisi Rancangan Undang-Undang Rebublik Indonesia
Tentang Wakaf.
b. Hasil Penelitian, yaitu Laporan Penelitian Hukum Tentang Aspek
Hukum Wakaf Dalam Pembangunan Hukum Nasional, Tim Badan
Pembinaan Nasional.
c. Karya tulis dalam bentuk buku-buku bidang hukum wakaf, syari‟ah
Islam dan bidang-bidang ilmu lainnya;
3. Bahan Kepustakaan Tersier yang terdiri dari kamus bahasa Arab, kamus
Istilah Islam, Ensiklopedia digital dan bahan-bahan penunjang lainnya
yang memberikan petunjuk yang menjelaskan mengenai bahan-bahan
kepustakaan yang telah disebutkan diatas, seperti indeks situs umum
internet, dan indeks situs agama Islam yang terdapat dijaringan Internet.
Sedangkan untuk data skunder yang dilakukan dalam penelitian
ini diantaranya dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap pihak
terkait dalam hal ini Badan Wakaf Indonesia yang memiliki kewenangan
dalam pengelolaan wakaf di Indonesia.
Pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan yang
yang peneliti lakukan menggunakan dua cara yaitu:
1. Penelitian lapangan, yaitu penelitian langsung dilapangan untuk
mengetahui bagaimana pengaturan perbankan syari‟ah dalam
pengelolaan wakaf uang. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini
adalah melakukan wawancara kepada Direktur Eksekutif Badan Wakaf
Indonesia dan Ketua Divisi Kelembagaan Direktorat Jenderal
Peraturan Pemerintah.
2. Penelitian kepustakaan, adalah penelitian untuk penyusunan kerangka
sebagai landasan analisis. Teknik yang dipakai dalam dalam penelitian
ini dengan cara menelaah badan-badan hukum baik yang berupa
perUndang-Undangan maupun literatur-literatur terkait.
25
Universitas Indonesia
Data yang telah terkumpul kemudian diolah secara sistematis
kemudian dianalisis berdasarkan sifat data. Data kualitatif dianalisis secara
deskriptif, yaitu data yang telah terkumpul diklasifikasikan kemudian
ditafsirkan secara rasional dan objektif kemudian digambarkan secara
logis. Analisis terhadap data penelitian di atas dilakukan secara kualitatif
sehingga dapat diperoleh hasil data yang berguna bagi penilaian terhadap
perangkat hukum yang diteliti.
1.12. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam
menyusun penelitian ini diperoleh dengan cara studi dokumen atau setudi
kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan peneliti menggunakan berbagai
literatur berupa peraturan perUndang-Undangan, buku-buku karya ilmiah,
makalah kuliah yang terkait langsung dengan wakaf dan perbankan, asas-asas
keadilan, asas-asas keseimbangan, istikhsan, maslahah mursalah dan data
sekunder lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti.
1.13. Sistematika Penelitian
Untuk menyusun tesis ini, peneliti akan menguraikan masalah yang akan dibagi
dalam dalam 5 bab. Adapun pembagiannya kedalam bab-bab nanti adalah sebagai
berikut:
BAB I PENDAHULUAN, bab ini merupakan bab pendahuluan yang
berisikan antara lain: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Manfaat
Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka pemikiran, Metode
Penelitian, Jenis penelitian, Pendekatan Masalah, Sumber Data Penelitian, Teknik
dan Alat Pengumpulan Data, Sistematika Penelitian.
BAB II. TINJAUNAN UMUM TENTANG WAKAF, didalam bab ini
berisi tentang Pengertian Wakaf: Dasar Hukum Wakaf: Fungsi dan Tujuan
Wakaf: Rukun dan Syarat Wakaf: Syarat Jangka Waktu Wakaf Macam-macam
Wakaf Status Harta Wakaf Hakikat Harta Benda Wakaf:
26
Universitas Indonesia
BAB III. TINJAUNAN UMUM TENTANG PERBANKAN SYARI‟AH,
didalam bab ini berisi tentang Pengertian Bank Syari‟ah: Dasar Hukum Bank
Syari‟ah: Fungsi dan Tujuan Bank Syari‟ah: Rukun dan Syarat Bank Syari‟ah:
Ruang lingkup Perbankan Syari‟ah: Macam-macam Bank Syari‟ah: Status Harta
didalam Bank Syari‟ah: Konsep perbankan syari‟ah: Fungsi dan Peran perbankan
Syari‟ah: Produk Perbankan Syari‟ah: Aspek Hukum Pembiayaan;
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yang akan
menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan
pembahasannya yaitu Peran Bank Syariah Dalam Pengelolaan Wakaf Uang serta
apasaja kendala yag dihadapi Bank Syariah untuk menjadi Nadzir Wakaf.
BAB V PENUTUP, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan
saran dari hasil penelitian ini.
27 Universitas Indonesia
BAB 2
TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF
2.1. Pengertian Wakaf
2.1.1 Pengertian menurut bahasa
Secara bahasa wakaf berasal dari bahasa arab al-Waqf bentuk masdar dari
kata waqafa-yaqifu-wakfan1. Kata al-Waqf semakna dengan kata al-Habs bentuk
masdar dari kata habasa-yahbisu-habsan artinya menahan.2 Berbagai pengertian
wakaf diatas dapat disimpulkan bahwa al-Habs maupun al-Waqf sama sama
mengandung makna menahan, mencegah atau melarang dan diam. Dikatakan
menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan
yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf.
2.1.2 Pengertian Menurut Istilah
Secara istilah para ulama berbeda-beda mengartikan wakaf ini sesuai dengan
mazhab yang mereka anut.3 Secara umum para ulama dalam mendefinisikan
Wakaf merujuk pada Imam Mazahibul Arbaah yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki,
Imam Syafi‟i dan Imam Hambali. Adapun pendapat para Imam Mazahib ini
adalah sebagai berikut:
2.1.2.1. Menurut Golongan Hanafi:
Imam Syarkhasi mendefinisikan wakaf yaitu “menahan harta dari
jangkauan kepemilikan orang lain (habsul mamluk‟an al-tamlik min al-
1 A.W.Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Surabaya:Pustaka
Progressif, Cet.Ke-14, 1997, hlm. 1576.
2 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 3, Beirut: Daar Al-Fikr, t.th,hlm. 515
3 Anshori Abdul Ghofur, Hukum Dan Praktek Perwakafan Di Indonesia, Cet. 1
Yogyakarta: Pilar Media, 2005, hal,7.
28
Universitas Indonesia
ghair)”. Kata harta milik maksudnya memberikan batasan bahwa wakaf
terhadap tanah yang tidak bisa dianggap milik akan membatalkan wakaf.
Sedangkan kalimat “dari jangkauan kepemilikan orang lain (an al-tamlik min
al ghair)” maksudnya harta yang akan diwakafkan itu tidak boleh
dimanfaatkan untuk kepantingan wakif, seperti halnya jual beli, hibah atau
jaminan.
2.1.2.2.Menurut Golongan Maliki
Ibnu Arafah mendefinisikan wakaf “memberikan manfaat sesuatu pada
batas waktu keberadaanya bersama tetapnya wakaf dalam kepemilikan si
pemiliknya meski hanya perkiraan (pengandaian)”
Memberikan manfaat sesuatu maksudnya adalah mengecualikan
pemberian barang seperti hibah. Orang yang berhibah berarti memberikan
barang kepada orang yang dihibahkan. Sedangkan pada wakaf yang diberikan
adalah manfaatnya, bukan barangnya. Kalimat “kepemilikannya tetap
dipegang oleh pemberi wakaf” adalah kalimat penjelas yang mengandung
maksud bahwa orang yang diberi wakaf ibarat hamba yang melayani tuannya
hingga meninggal. Maksudnya sipenerima wakaf itu tidak mempunyai hak
atas benda wakaf yang dijaganya itu, tetapi boleh menjualnya jika diizinkan
oleh sipemberi (wakif). Kalimat “walaupun dengan perkiraan” maksudnya
adalah bahwa lafal itumenunjukkan maksud kepemilikan. Dalam hal ini
ulama malkiyah membolehkan wakaf yang bersyarat.
2.1.2.3. Menurut Golongan Syafi’i
Muhammad Khatib Asy-Syarbini dalam kitab al-Mughni al-Muhtaj
mengartikan wakaf adalah:
دجظ بي ميى االزفبع
ث غ ثمبء ػ١ ثمغغ
ازصشف ىف سلجز ػ
صشف جبح جد
29
Universitas Indonesia
“menahan harta yang dapat di ambil manfaatnya dengan tetap utuhnya
barang dan barang itu lepas dari penguasaan wakif serta dimanfaatkan
pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama”4
2.1.2.4. Menurut Golongan Hanabilah, Syi’ah dan Ja’fariyah
Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughny al-Muhtaj menjelaskan bahwa
wakaf adalah:
حتجظ االص رغج١
ادلفؼخ
“menahan yang asal dan memberikan hasilnya”5
2.1.2.5. Menurut Ulama Zaidiyah
Pengarang kitab al-Syifa mendefinisikan wakaf sebagai:
“pemilikan khusus dan niat baik mendekatkan diri kepada Allah SWT”.
Kalimat “pemilikan khusus” artinya bukan pegadaian, penyewaan,
dipaksa, atau terpaksa. Sedangkan kalimat “dengan niat baik
mendekatkan diri kepada Allah SWT” hal itu tidak disyaratkan pada
sesuatu selain pada wakaf.6
2.1.2.6. Menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini
Dalam kitab Kifayatul al-Akhyar mendefinisikan wakaf lebih menekankan
pada tujuannya yaitu:
دجظ بي ميى االزفبع ث
غ ثمبء ػ١ ممع
4 Muhammad Khatib Asy-Syarbini, Mughny al-Muhtaj, Juz II, Beirut: Daar al-Fikr, t.th,
hlm.376.
5 Ibn Qudamah, Al-Mughny, Beirut: Daar al-Kitab al-Ilmiah, t.t, hlm. 185.
6 Anshori Abdul Ghofur, Hukum Dan Praktek Perwakafan Di Indonesia, Cet. 1
Yogyakarta: Pilar Media, 2005, hlm. 10.
30
Universitas Indonesia
ازصشف ىف ػ١ رصشف
بفؼخ ىف ارب رمشثب اىل
اهلل رؼبىل “menahan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekal
dzatnya, dilarang untuk digolongkan dzatnya dan dikelola manfaatnya”7
2.1.2.7. Dalam Ensiklopedi Islam
Waqf adalah memberikan harta kekayaan dengan sukarela atau suatu
pemberian yang berlaku abadi untuk kepentingan pemerintah Islam, untk
kepentingan keagamaan atau untuk kepentingan umum.8
2.1.2.8. Rumusan yang termuat dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang
Wakaf Pasal 1 point 1 dinyatakan, bahwa “wakaf adalah perbuatan
hukum wakif untuk memisahkan dan /atau menyerahkan sebagian
harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk
jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan
ibadah dan /atau kesejahtraan umum menurut syari‟ah9
2.1.2.9. Muhammad Daud Ali menyatakan, wakaf adalah menahan sesuatu
benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam.10
Dari berbagai pengertian wakaf diatas, maka wakaf dapat diartikan sebagai
melepaskan sebagian harta miliknya untuk keperluan umum dan peribadatan.
Berarti harta wakaf tersebut tidak diperbolehkan menjadi objek transaksi, hanya
manfaat atau hasilnya yang boleh diambil sesuai dengan peruntukan wakaf
sebagaimana tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf dan dengan jangka waktu
tertentu.
7 Abi Bakr Ibn Muhammad Taqiuddin, Kifayatul akhyar, Serikat an-nur Asia, hlm. 319
8 Cyril Glasse, Ensiklopedi Islam (Ringkas), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 2,
1999, hlm. 432.
9Kementerian Agama Rebublik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2011, hlm.2
10 Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Cet. 1 I Press, Jakarta:
2006, hlm. 90.
31
Universitas Indonesia
Berdasarkan definisi wakaf yang telah dikemukakan di atas maka cakupan
wakaf meliputi:
1. Harta benda milik seseorang atau kelompok orang.
2. Harta benda tersebut barsifat kekal dzat-nya tidak habis apabila dipakai.
3. Harta tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh sang pemiliknya.
4. Harta yang dilepaskan kepemilikannya tersebut tidak bisa dihibahkan,
diwariskan atau diperjual-belikan.
5. Manfaat dari harta banda tersebut untuk kepentingan umum sesuai syari‟at
Islam.11
2.2 Dasar Hukum Wakaf
Salah satu pranata sosial Islam yang mengandung nilai sosial ekonomi
adalah lembaga wakaf sebagai kelanjutan dari ajaran tauhid, yang berarti bahwa
segala sesuatu berpuncak pada kesadaran akan adanya Allah SWT. Lembaga
wakaf adalah salah satu bentuk perwujudan keadilan sosial dalam Islam, yaitu
didasarkan pada pemahaman bahwa harta yang dimiliki atau diperoleh adalah
rizki dari Allah yang didalamnya terdapat hak orang lain.
Sebagaiman Allah berfirman dalam al Qur‟an surat al-Baqarah ayat 2-3
Artinya :Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka
yang bertaqwa, (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang
mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki12
yang Kami anugerahkan
kepada mereka.13
Di dalam al Qur‟an surat at-Taubah ayat 103 juga disebutkan
11
http://www.wakafcenter.com/baca-optimalisasi-fungsi-perbankan-syariah-sebagai-
nadzir-investasi-wakaf.html, Optimalisasi Fungsi Perbankan Syari‟ah Sebagai Investasi Wakaf,
diakses 7 Mei 2014.
12 Rezki: segala yang dapat diambil manfaatnya. menafkahkan sebagian rezki, ialah
memberikan sebagian dari harta yang telah direzkikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang
disyari'atkan oleh agama memberinya, seperti orang-orang fakir, orang-orang miskin, kaum
kerabat, anak-anak yatim dan lain-lain.
13 Al-Qur‟an dan Terjemahnya, Mujamma‟ al Khadim al Haramain asy Syarifain al Malik
Fadhli Thiba‟at al Mushhaf asy Syarif, Madinah al Munawwarah, 1411 H., hlm. 8.
32
Universitas Indonesia
Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo‟alah untuk mereka.
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah
Maha mendengar lagi Maha mengetahui.14
Kemudian di jelaskan dalam al-Qr‟an surat Adz-Zariaat ayat 19
Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta
dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.15
Dari ketiga ayat di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa salah satu ciri
daripada orang yang bertakwa adalah mau menafkahkan sebagian hartanya ke
jalan Allah, bahkan terdapat perintah untuk mengambil sedekah bagi orang miskin
dari orang yang mampu karena sebagian dari harta yang kita miliki terdapat hak
orang lain yang membutuhkan.
Prinsip kepemilikan harta dalam ajaran Islam mensyaratkan bahwa harta
tidak dibenarkan hanya dikuasai oleh sekelompok orang, karena akan melahirkan
eksploitasi kelompok kaya (minoritas) terhadap kelompok miskin (mayoritas)
yang akan menimbulkan kesenjangan sosial dan akan menimbulkan akibat-akibat
negatif yang beraneka ragam.16
Sebagaimana Allh SWT berfirman dalam al-
Qur‟an surat al-Hasyr ayat 7:
14
Ibid., hlm. 297. Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta
yang berlebih-lebihan kepada harta benda, zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati
mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.
15 Ibid., hlm. 859., Orang miskin yang tidak mendapat bagian Maksudnya ialah orang
miskin yang tidak meminta-minta.
16 Taufiq Hamami, Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional, (jakarta:
Tatanusa, 2003), hlm. 36
33
Universitas Indonesia
Artinya: Apa saja harta rampasan (fai‟) yang diberikan Allah kepada RasulNya
(dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah,
untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang
yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya
saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dan apa
yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.17
Sifat yang demikian itu diancam oleh Allah SWT dengan siksa yang
pedih, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur‟an surat at-Tabah ayat 34-35:
Artinya: Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak
menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa
mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu
dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan
punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang
kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa
yang kamu simpan itu."18
Walaupun didalam al-Qur‟an tidak membahas masalah wakaf dengan
tegas, namun ada beberapa nash al-Qur‟an dan Hadits yang menjadi dasar hukum
wakaf, yaitu ayat-ayat al-Qur‟an dan hadits Nabi yang memerintahkan agar
manusia selalu berbuat kebaikan. Wakaf bukan hanya merupakan bentuk ibadah
(hablum min Allah) semata, melainkan merupakan suatu bentuk amal kebajikan
17
Al-Qur‟an dan Terjemahnya, Mujamma‟ al Khadim al Haramain asy Syarifain al Malik
Fadhli Thiba‟at al Mushhaf asy Syarif, Madinah al Munawwarah, 1411 H., hlm. 859.
18 Ibid, hlm. 283.
34
Universitas Indonesia
kepada sesama (hablum minan nas) juga. Didalam ilmu fiqih disebut dengan
mu‟amalat dunyawiyyah oleh kerena itu al-Qur‟an maupun al-Hadits tidak pernah
berbicara sepesifik dan tegas mengenai wakaf itu. Dilihat dari kemu‟amalatan
Wakaf juga merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui harta benda, maka
para ulama memahami ayat-ayat al-Qur‟an maupun al-Hadits yang
memerintahkan pemanfaatan harta untuk kebajikan juga mencakup kebajikan
melalui wakaf. dimana didalam kitab-kitab fiqih ditemukan pendapat yang
mengatakan bahwa dasar hukum wakaf disimpulkan dari beberapa ayat al-Qur‟an
sebagai berikut:19
Al-Qur‟an surat Ali Imran ayat 92:
Artinya: kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna),
sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang
kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.20
Tafsir kalimat
Kalimat diatas terdiri dari empat penggalan kata yang satu samalainnya saling
menguatkan maknanya, yaitu:
Kamu sekali-kali tidak sampai) ربا اجش .1
kepada kebajikan (yang sempurna),
Imam Al-Baydlawi menafsirkan pangkal ayat ini dengan:
رجغا دم١مخ ارب از
وبي اخلري أ ربا ثش اهلل
از اشمحخ اشض اجلخ
19
Helmi Karim, Fiqih Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm 103
20 Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah al-Qur‟an, Al-Qur‟an Al-Karim, Terjemah,
Semarang: PT Tanjung Mas inti, 1992, hlm. 91.
35
Universitas Indonesia
Artinya: Tidak akan meraih nilai kebaikan yang hakiki, kebaikan yang sempurna.
Tidak akan menggapai kebaikan Allah berupa rahmat, rido dan surga).21
Di dalam hadits juga diterangkan pengertian “al-Birr” sebagai berikut:
ػ ااط ث عؼب اأصبس
لبي عأذ سعي ا ص ا
ػ١ ع ػ اجش ائص
فمبي اجش دغ اخك ائص
صذسن وشذ أ ب دبن ف
٠غغ ػ١ ابطDiriwayatkan dari al-Nawas bin Sim‟an al-Anshari mengatakan: Saya bertanya
kepada Rasul SAW tentang pengertian “ al-Bir” dan “al-Itsm”. Beliau bersabda
al-Birr itu adalah akhlaq yang baik. Sedangkan al-Itsm ialah apa yang paling
menarik di hatimu, yang kamu sendiri enggan diketahui orang. (Hr.al-Bukhari,
Muslim, Abu Dawud, al-Tirmidzi)22
Dengan demikian pangkal ayat ini mengandung makna bahwa manusia belum
masuk kepada kategori yang berakhlaq mulia sebelum menafkahkan harta yang
paling dicintainya (sebagaimana ayat berikutnya).
sebelum kamu) دز رفما ب رذج .2
menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai).
Menginfakkan harta yang sangat dicintai merupakan syarat meraih
keimanan yang hakiki. Iman perlu dibuktikan dengan pengorbanan.
Menginfakkan harta yang dicintai membuktikan bahwa kecintaan pada Allah dan
agama melebihi kecintaan pada segalanya.
Di dalam al-Hadis dijelaskan peristiwa setelah ayat diatas turun:
21
Tafsir al-Baydlawi, II, hlm.62.
22 Imam Bukhari dan Muslim, Shahih al-Bukhari, V hlm.312
36
Universitas Indonesia
به سض ا ػ ػ أظ ث
٠مي وب أث عذخ أوضش
اأصبس ثبذ٠خ بب وب
أدت أا إ١ ث١شدبء
وبذ غزمجخ اغجذ وب
سعي ا ص ا ػ١
٠ششة بء ع ٠ذخب
ف١ب ع١ت فب ضذ }
ربا اجش دز رفما ب
رذج {لب أث عذخ إ
سعي ا ص ا ػ١
ع فمبي ٠ب سعي ا إ
وزبث} ا رؼب ٠مي ف
ربا اجش دز رفما
ب رذج {إ أدت أا
إ ث١شدبء إب صذلخ
أسج ثشب رخشب ػذ ا
فضؼب ٠ب سعي ا د١ش شئذ
بي سائخ ره فمبي ثخ ره
بي سائخ لذ عؼذ ب لذ
ف١ب أس أ رجؼب ف
األشثني لبي أفؼ ٠ب سعي
ا فمغب أث عذخ ف
ألبسث ث ػ
37
Universitas Indonesia
Anas bin Malik menerangkan: Abu Thalhah adalah orang Anshar kaya yang
paling banyak memiliki kebun kurma di Madinah. Dia sangat mencintai Bairuha
(nama kebun) yang berhadapan dengan Masjid. Rasul juga sering pergi ke kebun
itu dan minum air segar dari mata airnya.
Tatkala turun ayat ربا اجش
دز رفما ب رذجAbu Thalhah berkata: Wahai Rasul, Allah telah menegaskan bahwa tidak akan
mendapatkan kebaikan kecuali menginfakkan apa yang dicintai; harta yang amat
saya cintai adalah kebun Bayruha, maka dengan ini saya sedekahkan karena
Allah. Saya mengharapkan kebaikannya di sisi Allah SWT. Gunakanlah wahai
Rasul sesuai kehendakmu. Rasul SAW bersabda: Bakh (kata-kata kagum), ini
adalah harta yang sangat baik yang sangat bernilai! Saya mendengar apa yang
kamu ucapkan! Saya berpendapat alangkah baiknya engkau berikan ke kerabatmu.
Dia mengatakan aku lakukan wahai Rasul! Kemudian Abu Thalhah
membagikannya ke kaum kerabat dan anak pamannya. (Hr. al-Bukhari dan
Muslim).23
Dan apa saja yang kamu) ب رفما شء .3
nafkahkan)
Hal ini bukan berarti menginfakkan harta yang harganya rendah, tidak bernilai di
sisi Allah. Apapun yang di infakkan di jalan Allah walau sedikit, tetap bernilai
terpuji di sisi Allah SWT. Dengan demikian infaq itu terdiri dari yang berkualitas
terbaik, dan ada pula yang nilainya biasa saja. Keunggulan infaq dapat ditinjau
dari beberapa aspek antara lain (1) dari sudut nilai manfaat harta yang diinfakan,
(2) dari sudut ke mana infaq diperuntukkan, (3) apa yang diharapkan atau apa
yang menjadi tujuan dengan berinfaq.24
maka sesungguhnya Allah mengetahuinya فإن الله به عليم .4
Allah SWT maha mengetahui apa yang diperbuat manusia,
Ayat yang selanjutnya yang berkaitan dengan Wakaf adalah:
23Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ja'fai, Shahih al-
Bukhari, V hlm.304
24 http://saifuddinasm.com/2013/01/08/ali-imran-92-meraih-kebajikan-dari-harta-yang-di-
cintai/, Saifuddin, Meraih kebijakan dari harta yang dicintai, diakses 6 Juli 2014.
38
Universitas Indonesia
QS. Al-Baqoroh ayat 267:
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian
dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan
dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu
menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya
melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah
Maha Kaya lagi Maha Terpuji.25
Al-Qur‟an Surat al Hajj (22) ayat 77:
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu,
sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat
kemenangan.26
Jika menelaah berbagai ketentuan Allah diatas, maka dapat dipahami
bahwa penyampaian perintah menjalankan wakaf adalah bersifat umum, yaitu
sebuah perintah untuk berbuat kebaikan. Kebaikan yang dimaksud adalah
mengandung dan mencakup pengertian zakat, infaq, shadaqoh dan juga perintah
wakaf. Wakaf dikakatakan sebagai suatu kebaikan karena wakaf merupakan
penyerahan harta benda untuk kepentingan sosial yang tujuannya semata-mata
untuk mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah dalam rangka mengharapkan
pahala darinya.27
25
Al-Qur‟an dan Terjemahnya, Mujamma‟ al Khadim al Haramain asy Syarifain al Malik
Fadhli Thiba‟at al Mushhaf asy Syarif, Madinah al Munawwarah, 1411 H., hlm. 67.
26
Ibid., hlm. 528.
27 Taufiq Hamami, Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional, Jakarta: PT
Tatanusa, 2003, hlm. 41-42.
39
Universitas Indonesia
Amalan Wakaf ini bernilai sedekahh jariah artinya kebaikannya akan
mengalir terus menerus secara berkesinambungan selama harta wakaf tersebut
diperuntukkan untuk kepentingan umum.28
Menurut pendapat Imam ar-Rafi‟i,
sedekah jariyah maknanya adalah wakaf, sebab sedekah selain wakaf pahalanya
tidak dapat terus mengalir, bahkan hanya terhenti ditangan penerima sedekah saja.
Sedangkan yang dimaksud dengan sedekah jariah adalah sedekah yang pahalanya
terus mengalir walaupun pelaku sedekah telah meninggal dunia. Sebagaimana
Rasulullah bersabda:
ػ أث ش٠شح أ سعي اهلل ص اهلل
إرا بد » لبي -ػ١ ع
اإلغب امغغ ػ ػ إال
صالصخ إال صذلخ جبس٠خ أ ػ
٠زفغ ث أ ذ صبخ ٠ذػ Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah saw
bersabda: Apabila seseorang meninggal dunia maka terputuslah semua amalannya
kecuali tiga, yaitu: Sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat atau anak
shalih yang mendo‟akan kepadanya.” (HR. Muslim)29
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketentuan-ketentuan dalam al-
Qur‟an itu dapat dijadikan sebagai dasar umum tentang peritah wakaf.
Dasar disyari‟atkannya wakaf adalah perintah Nabi kepada Umar bin
Khatab untuk mewakafkan tanah di Khaibar seperti yang tertuang dalam
percakapan Nabi dan Umar bin khatab dalam hadits riwayat Imam Muslim berikut
ini:
Al Hadits:
ػ اث ػش لبي أصبة ػش
ص -أسضب ثخ١جش فأر اج
28
Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet.6,
2003, hlm. 482.
29 Ibid, 14.
40
Universitas Indonesia
٠غزأش ف١ب -اهلل ػ١ ع
بي ٠ب سعي اهلل إ أصجذ فم
أسضب ثخ١جش أصت بال لظ
أفظ ػذ فب رأش ث
إ شئذ دجغذ أصب » لبي
لبي فزصذق ثب «. رصذلذ ثب
ال ػش أ ال ٠جبع أصب
٠جزبع ال ٠سس ال ٠ت. لبي
فزصذق ػش ف افمشاء ف
امشث ف اشلبة ف عج١
اهلل اث اغج١ اض١ف ال
جبح ػ ١ب أ ٠أو
صذ٠مب ب ثبؼشف أ ٠غؼ
غ١ش زي ف١ Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA, dia berkata: Umar telah mendapatkan
sebidang tanah di Khaibar, lalu dia datang kepada Nabi Salallahu Alaihi
Wasallam untuk meminta pertimbangan tentang tanah itu, kemudian dia berkata
wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar,
dimana aku tidak mendapatkan harta yang lebih berharga bagiku selain
daripadanya; maka apakah yang hendak engkau perintahkan kepadaku
sehubungan dengannya? Rasulullah Salallahu Alaihi Wasallam berkata kepada
Umar: jika engkau suka tahanlah tanah itu dan sedekahkan manfaatnya. Lalu
Umar pun menyedekahkan manfaat tanah itu dengan syarat tanah itu tidak akan
dijual, tidak akan dihibahkan dan tidak akan diwariskan. Tanah itu diwakafkan
kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan
tamu dan tidak ada halangan bagi orang yang mengurusnya untuk memakan
sebagian darinya dengan cara ma‟ruf dan memakannya tanpa menganggap tanah
itu miliknya sendiri.”30
30
Imam Muslim, Shahih Muslim, II: 13-14.
41
Universitas Indonesia
Selain hadits diatas, ditegaskan pula dalam hadits nabi yang menyinggung
tentang wakaf, yaitu:
ػ أث ش٠شح أ سعي اهلل ص اهلل
إرا بد » لبي -ػ١ ع
اإلغب امغغ ػ ػ إال
خ جبس٠خ أ ػ صالصخ إال صذل
٠زفغ ث أ ذ صبخ ٠ذػ
]سا غ[ «. Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah saw
bersabda: Apabila seseorang meninggal dunia maka terputuslah semua amalannya
kecuali tiga, yaitu: Sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat atau anak
shalih yang mendo‟akan kepadanya.” (HR. Muslim)31
Menurut Sayyid Abi Bakr dalam kitab I‟anah at-Talibin, menjelaskan bahwa:
اصذلخ اجلبس٠خ حمخ ػذ
اؼبء ػ
الف.............
Artinya: Menurut para Ulama shadaqah jariah ini dikatagorikan dalam wakaf.32
Bahkan dalam lanjutan kalimat diatas, disebutkan:
31
Ibid, hlm.14.
32 Sayyid Abi Bakr bin Sayyid Muhammad, I‟anah at-Talibin, Juz III, Mesir : Musthofa al-
Babi al-Khalbi wa Auladuhu bi Misri, 1342, hlm. 157
42
Universitas Indonesia
فب غري اصذلبد ١غذ
ث مبه ادلزصذق جبس٠خ
ػ١
Artinya: Maka sesungguhnya shadaqah yang lainnya (selain wakaf) bukan
merupakan sedekah jariah(sedekah yang pahalanya mengalir terus), karena hanya
terhenti ditangan penerima sedekah saja.”33
Hal yang sama dikemukakan oleh Imam ar-Rafi‟i, bahwasanya sedekah jariyah
maknanya adalah wakaf, sebab sedekah selain wakaf pahalanya tidak dapat terus
mengalir, bahkan hanya terhenti ditangan penerima sedekah.34
Sehingga jelas
maksud dari shadaqah adalah wakaf. Karena pahala wakaf akan terus menerus
mengalir selama harta benda wakaf masih dimanfaatkan. Sebagaimana ketentuan
sedekah jariah yang manfaat dan pengaruhnya kekal setelah pemberi sedekah
meninggal dunia.35
Al-Qur‟an dan Hadits diatas adalah dalil yang mendasari disyari‟atkannya
wakaf sebagai tindakan hukum, baik kepentingan sosial maupun kepentingan
keagamaan dengan maksud memperoleh pahala dari Allah SWT. Memang sedikit
sekali ayat-ayat al-Qur‟an dan al-Hadits yang menyinggung tentang Wakaf,
sehingga sedikit pula hukum-hukum wakaf yang ditetapkan dengan kedua sumber
hukum itu. Walaupun demikian ternyata tidak menyurutkan para fuqaha untuk
berijtihad membuat pedoman tentang wakaf tersebut berdasarkan sumber hukum
yang ada. Sejak masa khulafa‟ur Rasyiddin sampai para fuqoha‟ terus melakukan
ijtihad tentang hukum wakaf. Oleh karena itu sebagian besar hukum-hukum
33
Ibid
34 http://wakafpro99.org/?page_id=614
35 Yusuf Qordhowi, Fii Fiqh al-Aulawiyyaati Dirasah Jadiidah fii Dhau‟ al-Qur‟ani wa as-
Sunnati, Terj. Muhammad Nurhakim “Urutan Amal Yang Terpentnig Dari Yang Penting”, Jakarta:
Gema Insani Pers, 1996, hlm.123
43
Universitas Indonesia
wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad36
, dengan menggunakan
metode yang bermacam-macam seperti Qias, Maslahah Mursalah dan lain-lain.37
Oleh karena itu, ketika hukum (ajaran) Islam masuk ke ranah ijtihadi,
maka hal tersebut menjadi sangat fleksible, artinya sangat terbuka terhadap
penafsiran-penafsiran baru, dinamis dan futuristik (ber-orientasi pada masa
depan).38
2.3 Fungsi dan Tujuan Wakaf:
Sebagaimana disyari‟atkan dalam dasar-dasar hukum wakaf diatas, baik
yang terdapat dalam al-Qur‟an maupun al-Hasits, terdapat banyak keutamaan
dalam perbuatan wakaf. keutamaan wakaf tersebut adalah sebagai berikut:39
a. Wakaf menanamkan sifat zuhud40
dan melatih menolong kepentingan orang
lain.
b. Menghidupkan lembaga-lembaga sosial maupun keagamaan demi syi‟ar
Islam dan keunggulan kaum muslimin.
c. Menanamkan kesadaran bahwa didalam setiap harta benda, meski telah
menjadi milik sah, mempunyai fungsi sosial.
d. Wakaf menyadarkan seorang bahwa kehidupan diakhirat memerlukan
persiapan yang cukup. Wakaf merupakan tindakan hukum yang menjanjikan
pahala yang berkesinambungan.
Fungsi pokok dari wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat
ekonomis harta benda wakaf dan harus sesuai dengan fungsinya. Agar manfaat
harta benda wakaf dapat mengalir terus menerus dalam masyarakat maka benda
36
Ijtihad adalah berpikir keras untuk menghasilkan pendapat hukum atas suatu masalah
yang tidak secara jelas disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnahlm. Pelakunya disebut Mujtahid
( orang yang berkompeten untuk melakukan ijtihad dengan syarat-syarat khusus)
37 Depag, Fiqih Wakaf, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005, hlm.
38 Depag, Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, Jakarta: Proyek Peningkatan
Pemberdayaan Wakaf, Dirjen bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004, hlm. 59.
39 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Cet.3 PTRaja Grafindo Persada, Jakarta: 1959
hal, 487
40 zuhud secara istilah berarti tidak mementingkan hal - hal yang bersifat keduniawian, atau
meninggalkan gemerlap kehidupan yang bersifat material dalam mengabdikan diri kepada Allah
subhanahu wa ta'ala
44
Universitas Indonesia
wakaf tersebut harus dikelola dengan baik , sesuai dengan fungsi dan tujuan orang
yang berwakaf (wakif). Tujuan utama dari wakaf adalah untuk mencari keridhaan
Allah SWT, oleh karena itu, tidak diperbolehkan menyimpang dari nilai-nilai
ibadah misalnya mewakafkan tanah untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran
Islam.41
2.4 Rukun dan Syarat Wakaf:
Para mujtahid berbeda-beda dalam merumuskan definisi wakaf, namun
mereka sepakat dalam pembentukan wakaf diperlukan berbagai syarat dan rukun.
Syarat menurut etimologi (bahasa) berarti tanda,42
namun menurut
terminologi (istilah) syarat adalah:
جد احلى ػ لفب ٠ز
جد ٠ض ػذ ػذ
احلى
Artinya: “sesuatu yang tergantung pada hukum syar‟i yang keberadaannya diluar
hukum itu sendiri dan ketiadaannya menyebabkan keberadaan hukum-hukum itu
hilang”43
Dengan kata lain, sesuatu yang karenanya baru ada hukum dan karena
ketiadaannya tidak ada hukum.44
Sedangkan rukun adalah sesuatu yang merupakan sendi utama dan unsur
pokok dalam pembentukan suatu hal. Perkataan rukun berasal dari bahasa arab
41
Deby Nuri Herasanti, Eksistensi Wakaf Menurut hukum Islam, Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 1977, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Thesis Program Magister
Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2006, hlm.43
42 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, Daar Al-Kutub, 1968, hlm. 118.
43 Muhammad Rifa‟i, Ushul Fiqh, Semarang : Wicaksana, 1991, hlm.15
44.Ibid.
45
Universitas Indonesia
“ruknu” yang berarti tiang, penopang atau sandaran.45
Menurut istilah rukun
adalah sifat yang tergantung keberadaan hukum padanya dan sifat itu yang
termasuk kedalam hukum itu sendiri.46
Atau dengan kata lain rukun adalah
sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perbuatan. Dengan demikian
sempurna atau tidaknya wakaf dipengaruhi oleh beberapa rukun yang ada dalalam
perbuatan wakaf tersebut. Masing-masing rukun tersebut harus saling menopang
satu dengan lainnya, karena keberadaan yang satu sangat menentukan keberadan
yang lainnya.
Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya.
Adapaun rukun wakaf ada empat yaitu:47
1. Wakif (orang yang berwakaf)
2. Maukuf bih (harta wakaf)
3. Maukuf alaih (tujuan wakaf)
4. Sighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk
mewakafkan sebagian harta benda miliknya)
Namun bila kita melihat Undang Undang wakaf yang kita miliki yaitu UU No.41
Tahun 2004 Pasal 6 menambahkan hukum wakaf dengan:48
1. Nadzir (pengelola Wakaf)
2. Jangka waktu wakaf.
Dari tiap rukun wakaf diatas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Syarat Wakif
Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkanmemiliki kecakapan hukum
atau kamalul ahliyyah (legal competent) dalam membelanjakan hartanya.
Kecakapan bertindak disini meliputi empat kriteria,49
yaitu:
a. Merdeka;
45
Anton M. Mulyono, et al., Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. Ke-2, Jakarta: Balai
Pustaka, 1989, hlm.757.
46 Nasrun Harun, Ushul Fiqh I, Jakarta: 1996, hlm. 246
47 Farida Prihatini, et al., Hukum Islam Zakat dan Wakaf, Jakarta: Papas Sinar Kinanti dan
Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), 2005, hlm. 110-111
48 Hadi Setya Tunggal, Op.Cit., hlm. 10.
49 Depag Fikih Wakaf, Op.Cit., hlm. 21-22.
46
Universitas Indonesia
b. Berakal sehat;
c. Dewasa (baligh); dan
d. Tidak berada dibawah pengampuan (boros/ lalai).50
2. Syarat mauquf bih (harta Wakaf)
Syarat yang harus dpenuhi harta benda wakaf adalah sebagai berikut:
a. Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak habis
sekali pakai;
Mayoritas ulama berpendapat, benda yang diwakafkan itu sifat zatnya
kekal atau tahan lama, tidak cepat habis seperti makanan dan lain-lain.
Jika diperhatikan, barangkali itu sebabnya contoh-contoh yang terjadi
pada masa rasul umumnya benda yang tahan lama dan kekal zatnya.51
.
sehingga dapat disimpulkan bahwa barang yang dapat diperjual
belikan dapat diwakafkan tanpa menghabiskan barangnya, artinya
tidak sah berwakaf suatu benda apabila benda itu tidak dapat diambil
manfaatnyamelainkan dengan merusaknya. Oleh kerena itu barang
yang dilarang diperjual-belikan seperti barang-barang haram dan
barang yang cepat habis kalau dimanfaatkan, atau barang-barang yang
cepat rusak maka tidak sah dijadikan wakaf.52
b. Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum ; dalam
kitab Raad al-Mukhtar, disebutkan:
Artinya: begitu juga sah wakaf Musya‟(badan Hukum) ia memutuskan
kebolehannya”53
c. Benda wakaf merupakan benda milik yang sempurna. Ia terbebas dari
segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa; sebagaimana
dikatakan oleh Wahbah Zuhaili:
Artinya: hendaknya benda wakaf itu milik wakif secara sempurna
(tanpa ada pembebanan pada saat mewakafkannya)
50
Ibrahim al-Bajuri, Loc.Cit.
51 Abdul Hakim, Hukum Perwakafan Di Indonesia, Ciputat: Ciputat press, 2005, hlm. 20.
52 Ibid.
53 Ibid.
47
Universitas Indonesia
d. Benda itu tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan ata dipergunakan
selain untuk wakaf. seperti yang telah dinyatakan oleh Sayyid Sabiq:
Artinya: Apabila wakaf telah tetap (mempunyai kekuatan hukum)
maka, tidak boleh menjualnya, menghibahkannya dan tindakan-
tindakan lain yang menghilangkan sifat wakafnya‟54
.
Benda wakaf sebagaimana dalam fiqih Islam meliputi berbagai benda
tetep dan benda bergerak, meski berbagai riwayat/Hadts yang
menceritakan masalah wakaf adalah mengenai tanah, tetapi berbagai
ulama memahami wakaf selain tanah diperbolehkan saja, asalsaja zat
benda itu an sich tetap atau tahan lama. Maksudnya bukan barang
cepat habis bila dipakai atau diambil manfaatnya.55
hal ini sejalan
dengan fikih Islam yang berkembang dalam Ahlussunnah, dikatakan
“sah kita mewakafkan binatang” demikian juga pendapatnya imam
Ahmad dan Imam Malik.56
Dari sini dapat penulis simpulkan bahwa
benda wakaf adalah benda-benda baik bergerak maupun tidak bergerak
yang tidak cepat habis apabila diambil manfaatnya.
3. Syarat Mauquf Alaih (Tujuan Wakaf)
Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan
diperbolehkan menrut syari‟at Islam. Karena pada dasarnya wakaf
merupakan suatu ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada
Allah. Tujuan wakaf merupakan wewenang Wakif . apakah harta wakaf
tersebut ditujukan untuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf
keluarga (Wakaf Ahli) atau untuk fakir miskin dan lain-lain, atau untuk
kepentingan Umum (Wakaf Khairi).57
Tentu saja dalam hal ini sama-sama
untuk menghindari penyalahgunaan harta benda wakaf. jelasnya syarat
dari tujuan wakaf adalah untuk:
54
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, juz III, Beirut: Daar al-Kitab al-Araby, 1971, hlm.552
55 Raihan Rasid, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: Bulan Bintang, Cet.ke-5, 1978,
hlm. 179.
56 Raihan Rasid, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, Cet,
ke-10, 2003, hlm. 38.
57 Ahmad Rofiq, Fikih Kontekstual: Dari Normative Ke Pemahaman Sosial, Semarang:
Pustaka Pelajar, 2004, hlm.323.
48
Universitas Indonesia
a. Kebaikan;dan
b. Mencari keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepedaNya.
Sehingga tujuan wakaf tidak di benarkan dengan peruntukan maksiat atau
membantu mendukung dan /atau untuk tujuan maksiat.
4. Syarat Shighat (Ikrar)
Ikrar Wakaf ialah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan
dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.58
Terdapat tiga pendapat yang berbeda dari kalangan ulama tentang perlu atau
tidaknya qobul (penerimaan) dalam dalam sighat akad. Pendapat pertama,
mewajibkan adanya qobul (sighat penerimaan) secara mutlak baik wakaf untuk
umum maupun wakaf untuk pihak tertentu. Kedua, tidak mensyaratkan Qobul
secara mutlak dan ketiga membedakan antara wakaf untuk umum (menrut
pendapat ke tiga tidak perlu adanya Qobul ) dan wakaf bagi pihak tertentu perlu
adanya Qobul.59
Menurut Imam Syafi‟i didalam kitab al-Umm disebutkan:
ز اؼغ١خ رز ثأش٠ :
اشبد أػغب ب لجضب
ثأش أػغب بArtinya: dan pemberian wakaf ini akan sempurna dengan memenuhi dua perkara
yait pengakuan yang memberikan dan penerimaan bagi yang menerima dengan
perintah yang memberikan.60
Pernyataan Imam Syafi‟i diatas menunjukkan, bahwa syarat syahnya
wakaf adalah adanya Ijab dan Qobul. Sedangkan ulama yang berpendapat
berlainan dengan Imam Syafi‟i diantaranya Imam Muhammad Jawaad
Mughniyah, beliau mengatakan bahwa Mazhab Hambali dan Mazhab Hanafi
sepakat jika wakafnya itu untuk kepentingan umum tidak membutuhkan adanya
qabul, demikian pula wakaf untuk pihak tertentu (khusus) juga tidak
58
Hadi Setya Tunggal, Loc.Cit.
59 Muhammad Jawad Mughniyah, Al-Fiqh Ala al-Mazahib al-Khamsah, Terj. Masykur,
Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, “Fiqih Lima Mazhab”, Jakarta, 2001, hlm. 642.
60 Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris as-Syafi‟I, Al-Umm, juz 4, Bairut: Dar al-
Kutub al-Ilmiah, t.thlm., hlm. 53.
49
Universitas Indonesia
membutuhkan qabul.61
Hal yang sama juga dikemukakan oleh Imam Zakariyya
al-Anshori dalam kitab Fath al Wahab bahwa ikrar wakaf cukup dengan ijab saja
dari wakif tanpa memerlukan qabul dari mauquf „alaih, sebagaimana telah
dikatakan oleh Imam Zakariyya al-Anshori dalam kitab Fath al Wahab:
)اللجي( فال ٠شرتط )
ؼني ( ظش اىل ا لشثخ
Artinya: “Maka tidak disyaratkan adanya Qobul, Walaupun dari sesuatu yang
nyata(jelas), karena sesungguhnya wakaf adalah Ibadah Untuk mendekatkan diri
kepada Allah”62
Pernyataan ini menunjukkan bahwa ikrar wakaf merupakan tindakan
hukum yang bersifat deklaratif (sepihak). Untuk itu tidak diperlukan adanya qobul
dari orang yang menikmati manfaat wakaf. karena fungsi ibadah wakaf adalah
pendekatan diri kepada Allah SWT.
Begitupun Sayid Sabiq, beliau berpandangan bahwa Wakaf itu hanya
membutuhkan Ijab dan tidak membutuhkan Qabul. Sebagaimana yang beliau
tuliskan dalam kitab Fiqh al-Sunnah,
ػ ىت فؼ االف ب ٠ذي
الف ا غك ثبص١غخ ض
ف ثششط ا ٠ى االف ال
ثأ ٠ى وب شفصمم ٠صخ ر
اؼم اجؽ األ١خ
61
Muhammad Jawad Mughniyah, al-Fiqh Ala al-Mazahib al-Khamsah, Terj. Masykur,
Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, “Fiqih Lima Mazhab”, Jakarta, 2001, hlm. 642.
62 Abu Yahya Zakariya al-Anshori, Fath al-Wahab, Juz I, Semarang: Toha Putra, t.thlm.,
hlm. 257.
50
Universitas Indonesia
احلش٠خ االخز١بس ال حيزبط ىف
اؼمبد إىل لجي ادللف ػ١
Artinya: bila seorang yang berwakaf berbuat sesuatu yang menunjukkan kepada
wakaf, maka terjadilah wakaf itu, dengan syarat orang yang berwakaf adalah
orang yang sah tindakannya, misalnya telah sempurna akalnya, dewasa, merdeka,
dan tidak terpaksa.63
Untuk itu menurut Sayyid Sabiq bahwa terjadinya wakaf tidak perlu
adanya qabul dari orang yang menerima wakaf.
Alasan Sayyid Sabiq bahwa wakaf tidak perlu adanya qabul adalah
sebagai berikut:
٠صخ الف ٠ؼمذ ثأدذ
( افؼ : اذاي ػ١ 1أش٠
٠جين غجذا ٠ؤر صالح : وأ
2ف١ ال حيزبط إىل دى دبو.
( امي: ٠مغ إىل صش٠خ
ف : لفذ اال: ض لي
دجغذ عجذ أثذد. اىب٠خ
: وب ٠مي: رصذلذ ب٠ب ث
الف. اب الف ادلؼك
أ ثبدلد ض ا ٠مي: داس
فشع لف ثؼذ ر " فئ
جبئض ره ىف ضبش زت امحذ,
وب روش اخلشل غري,٢ زا
ذ١ئز و اصب٠ب ف
63
Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, juz I Kairo: Maktabah Dar al-Turus, tt, hlm. 309.
51
Universitas Indonesia
ازؼ١ك ثؼذ ادلد ٠م
ص١خ. جبئضا أل
Artinya: wakaf itu sah dan terjadi melalui dua perkara:
a. Perbuatan yang menunjukkan padanya; seperti bila seseorang membangun
masjid, kemudian azan untuk mendirikan shalat berjamaah didalamnya
perilaku orang tersebut tidak memerlukan keputusan hakim untuk
melakukan hal itu.
b. Ucapan: ucapan ini ada dua macam yaitu Sharikh (tegas) dan ada yang
kinayah (tersembunyi). Yang sharikh misalnya ucapan seorang yang
mewakafkan: “aku wakafkan” , “aku hentikan pemanfaatannya”, “ aku
jadikan untuk sabilillah”, “aku abadikan”. Yang kinayah, seperti ucapan
seorang yang mewakafkan: “aku sedekahkan”, akan tetapi dia berniat
mewakafkannya. Adapun wakaf yang dihubungkan dengan kematian,
seperti seseorang berkata: “rumahku atau kudaku menjadi wakaf sesudah
aku mati”, maka hal itu diperbolehkan menurut Imam Zahiri dari mazhab
Ahmad, seperti yang telah disebutkan oleh Al-Khiraqi dan lain-lain. Sebab
ini semuanya termasuk kedalam wasiat; oleh karena itu ta‟liq kematian
untuk wakaf adalah diperbolehkan sebab wakaf adalah wasiat.64
Selain alasan yang telah dikemukakan di atas, alasan lain dari Sayyid Sabiq
bahwa wakaf tidak diperlukan adanya qabul dari penerima wakaf adalah:
1. Karena seseorang yang menunjukkan perilaku perbuatan wakaf atau
mengucapkan kata-kata wakaf, maka wakaf itu dianggap terjadi dengan
syarat orang yang berwakaf adalah orang yang sah tindakannya seperti
telah sempurna akalnya, dewasa, merdeka dan tidak dipaksa
2. Wakaf adalah perbuatan tabarru‟(mendamakan harta) sehingga tidak
membutuhkan Qabul.65
Walaupun pendapat para ulama tersebut menyatakan bahwa wakaf hanya
butuh ijab dan tidak butuh qabul, namun dalam pelaksanaanya wakaf tetap
membutuhkan bukti-bukti tertulis, agar tindakan hukum wakaf mempunyai
kekuatan hukum dan menciptakan tertib administrasi.
64
Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juz 3, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1970, hlm. 309.
65 Ahmad Rofiq, Fiqh Kontekstual, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 322.
52
Universitas Indonesia
Pernyataan tersebut menunjukkan, bahwa ikrar wakaf merupakan tindakan
hukum yang bersifat deklarasi (sepihak) oleh karena itu tidak diperlukan qobul
dari orang yang menikmati manfaat wakaf. Para fuqoha‟ telah menetapkan syarat-
syarat shighat (ikrar), sebagai berikut:
a. Shighat harus mengandung pernyataan bahwa wakaf itu bersifat kekal
(ta‟bid). Untuk itu wakaf yang dibatasi waktunya tidak sah.hal ini
sesuai dengan pendapat dari mazhab Syafi‟i yang menyatakan bahwa
wakaf diberikan dengan cara memutus hak pengelolaan wakif atas harta
benda wakaf. Lain halnya menurut mazhab Maliki yang tidak
mensyaratkan adanya ta‟bid sebagai sarat sah wakaf66
Berkaitan dengan jangka waktu tersebut dalam Undang-Undang Rebublik
Indonesia nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur ketentuan
wakaf dengan jangka waktu tertentu dalam hal harta benda wakaf
berupa benda bergerak. Dasar pemahaman diaturnya jangka waktu
wakaf dalam peraturan perundang-undangan tersebut adalah pendapat
dari Mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa Wakif masih menjadi
pemilik harta benda wakaf. dan juga pendapat dari Imam Maliki yang
menyatakan bahwa wakaf dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu
sesuai keinginan wakif.
b. Sighat harus mengandung arti yang tegas dan tunai;67
c. Shighat harus mengandung kepastian, maksudnya suatu wakaf tidak
boleh diikuti oleh syarat kebebasan memilih.
d. Sighat tidak boleh dibarengi dengan syarat yang membatalkan, seperti
mensyaratkan barang tersebut untuk keperluan maksiat.
5. Syarat Nadzir
Memang pada ketentuan fikih klasik nadzir wakaf tidak disebutkan
sebagai salah satu rukun wakaf, namun setelah memperhatikan tujuan
wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari hasil harta wakaf maka
keberadaan nadzir sangat diperlukan, bahkan menempati peran yang
66
Wahbah Zuhaili, Op.cit., hlm. 196
67 Ibid
53
Universitas Indonesia
sangat fital, sebab tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga
dan mengembangkan serta menyalurkan hasil atau manfaatnya dengan
tepat sasaran adalah kewajiban Nadzir. Maka dari itu UU Wakaf kita
mencantumkan bahwa Nadzir termasuk rukun dalam wakaf baik berupa
perorangan maupun berupa badan hukum.68
Adapun syarat yang harus dipenuhi bagi nadzir oerorangan adalah:
a. WNI
b. Beragama Islam
c. Dewasa
d. Amanah
e. Mampu secara jasmani dan rohani
f. Tidak tarhalang melakukan perbuatan hukum.
Adapun nadzir yang berbentuk organisasi maka syarat yang harus
dipenuhi adalah selain pengurus organisasi yang memenuhi persyaratan
nadzir perseorangan, organisasi tersebut harus bergerak dibidang sosial,
pendidikan, kemasyarakatan dan /atau keagamaan Islam. Tentunya
pengurus badan hukum yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan
nadzir perseorangan pula.69
2.5 Syarat Jangka Waktu Wakaf
Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang syarat keabadian waktu dalam
wakaf. Sebagian ulama mencantumkan jangka waktu sebagai syarat dan sebagian
ulama yang lain tidak mencantumkan. Ulama mazhab selain Maliki berpendapat
wakaf tidak akan terwujd kecuali bila orang yang mewakafkan bermaksud
mewakafkan barangnya itu untuk selama-lamanya dan terus menerus. Maka hal
itulah yang membuat wakaf disebut sebagai shdakah jariyyah.70
Sedangkan pada
sisi lain imam Maliki mengatakan “ wakaf tidak disyaratkan berlaku untuk
68
Hadi Setya Tunggal, Op.Cit., hlm.4.
69 Ibid., hlm. 6.
70 Muhammad Jawad mughniyyah, Al-Fiqh „Ala al-Mazahib al-Khamsah, Terj. Masykur, et
al.,”Fiqih Lima Mazhab”, Jakarta: Lentera, Cet.ke-5, 2000, hlm. 635-636.
54
Universitas Indonesia
selamanya, tetapi sah berlaku untuk jangka waktu satu tahun misalnya sesudah itu
harta wakaf itu kembali lagi kepada wakif” 71
Di dalam Kompilasi Hukum Islam, syarat “selama-lamanya” dicantumkan
pada Pasal 215 (1), bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seorang atau kelompok
orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan
melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan
umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.72
Namun kemudian syarat selama-
lamanya dalam KHI tersebut diubah seiring ditetapknnya UU Nomor 41/2004
pada Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “wakaf adalah perbuatan hukum
Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya
untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan
kepentingannya guna keperluan ibadah dan /atau kesejahteraan umum menurut
syari‟ah.73
2.6 Macam-macam Wakaf
Bila ditinjau dari segi peruntukan wakaf, maka lembaga wakaf menurut
doktrin hukum Islam ada dua bentuk, yaitu:
1. Wakaf Ahli
Wakaf ahli diseubt juga wakaf keluarga atau wakaf khusus, yang
dimaksud dengan wakaf ahli adalah wakaf yang ditujukan kepada orang
tertentu, baik keluarga wakif sendiri maupun orang lain.74
Bentuk wakaf
ahli ini dalam prakteknya mirip dengan lembaga Adat yang berbentuk
pusaka, hanya saja bedanya kalau wakaf Ahli pemberiannya tidak harus
ditujukan untuk keluarga wakaf atau keturunan, tetapi dapat diberikan
kepada siapa saja sesuai dengan keinginan si-Wakif, baik terhadap orang-
71
Ibid, hlm. 636.
72 Depag, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Dirjen Bimbingan Islam, 1999, hlm. 99.
73 Hadi Setya Tunggal, Loc.Cit.
74 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 244.
55
Universitas Indonesia
orang yang masih terkait hubungan kekeluargaan dengan si Wakif maupun
tidak.75
Wakaf seperti ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta
wakaf itu adalah orang-orang yang ditunjuk dalam ikrar wakaf.76
Satu sisi,
wakaf ahli ini baik sekali karena Wakif akan mendapatkan dua kebaikan,
yaitu kebaikan amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturrahminya
dengan orang yang di beri amanah wakaf. akan tetapi disisi lain wakaf ahli
ini sering menimbulkan masalah , sepaerti tatkala kalau anak yang
ditunjuk sudah tidak ada lagi keturunan, siapa yang berhak mengambil
manfaat dari harta tersebut. Lebih-lebih kalau pada saat pelaksanaan akad
wakafnya tersebut tidak disertai bukti tertulis yang dicatatkan kepada
negara.77
Menanggapi kenyataan ini dibeberapa negara melakukan
peninjauan kembali peraturan-peraturan mengenai pelaksanaan wakaf ahli,
seperti di Mesir pada tahun 1946 telah mengeluarkan undang-undang
dimana semua Wakaf Keluarga diubah bersifat sementara. Kemudian
pada tahun 1952 bentuk wakaf ahli ini di hapus sebagaimana yang
tertuang dalam Undang-Undang Mesir Nomor 180 tahun 195278
.
Penghapusan ini sebelumnya telah didahului dengan perdebatan sengit
oleh parlemen Mesir. Alasan penghapusan wakaf ahli adalah karena sering
terjadi penyalahgunaan terhadap wakaf ini seperti:
a. Wakaf ahli dijadikan sebagai alat untuk menghindari pembagian
warisan kepada ahli waris yang berhak manakala si Wakif nantinya
meninggal dunia.
75
Taufiq Hamami, Op.Cit.,hlm.66.
76 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 244.
77 Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, Perkembangan Pengelolaan Wakaf
di Indonesia (Jakarta: Departemen Agama, 2006), hlm. 42.
78 M Ubaid al-Kabisi, Ahkam al Waqf asy-Syar‟iah al Islamiyah, Baghdad : Al-Irsyad 1977
56
Universitas Indonesia
b. Wakaf ahli dijadikan alat untuk menghindari tuntutan-tuntutan
kreditor terhadap hutang-hutang yang dilakukan si Wakif sebelum ia
mewakafkan hartanya.79
Karena banyak praktik-praktik penyalah gunaan harta wakaf tersebut maka
beberapa negara Islam lainnya seperti Syria, Turki, Maroko dan Aljazair
menghapuskan wakaf ahli, sebab praktik penyimpangan ini dipandang
telah tidak sesuai lagi dengan ajaran Islam.80
2. Wakaf Khairi
Praktek wakaf khairi dalam kehidupan masyarakat dikenal dengan istilah
Sosial. Dikatakan demikian karena wakaf ini diberikan oleh si wakif agar
manfaatnya dapat dinikmati kalangan masyarakat secara umum, tidak oleh
orang-orang tertentu saja.81
Seperti mewakafkan tanah untuk mendirikan
masjid, mewakafkan sebagian kebun yang hasilnya dapat dipergunakan
untuk membina jamaah pengajian dan sebagainya82
Berdasarkan pada hadits umar bin khatab tentang tanah di khaibar, bahwa
wakaf tersebut untuk kepentingan umum, meskipun disebutkan juga untuk
sanak kerabatnya. Oleh kerena itu, titik tekan agar sanak keluarga umar
tidak sampai tidak turut serta menikmati hasil harta wakaf itu. Hal ini
dipandang sudah mencakup diwakili dengan kata “ untuk kepentingan
umum” hal ini karena makna kata “untuk kepentingan umum” itu sudah
mencakup siapasaja yang termasuk dalam golongan fakir miskin, baik
untuk keluarga umar maupun bukan.83
Wakaf khairi inilah yang
manfaatnya akan betul-betul dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat
luas, serta dapat dijadikan sebagai salah satu sarana dalam
79
Hj.Tjek Tanti, Jurnal Al-Irsyad, Jurusan BKI – FITK IAIN Sumatera Utara, Wakaf Ahli
dalam Konsep Fikih Tradisional
80 M.A. Mannan, Sertifikasi Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam, alih
bahasa Tjasmijanto dan Rozidayanti (Depok: CIBER dan PKTTI-UI,2001), hlm.34
81 Taufiq Hamami, Op.cit, hlm. 67-68
82 Depag Fikih Wakaf, Op.cit.,hlm 221-222
83 Abdul Ghafur Anshori, Op.cit., hlm.31-32
57
Universitas Indonesia
penyelenggaraan kesejahtraan sosial, baik dalam bidang sosial ekonomi,
kebudayaan maupun keagamaan sendiri.
Para Ulama mazhab Imamiyah sepakat bahwa wakaf pada jenis ini
tidak boleh dijual dan tidak boleh pula diganti sekalipun rusak dan hampir
binasa ataupun ambruk. Sebab bagi ulama imamiyah sebagian besar dari
mereka wakaf tersebut tidak ada pemiliknya. Artinya ia telah keluar dari
pemiliknya yang pertama menuju keadaan tanpa pemilik. Sesudah barang-
barang tersebut diwakafkan, keadaan persis sama dengan keadaan barang
umum barang-barang umum yang mubah lainnya yang boleh
dimanfaatkan siapa saja.
2.7 Status Harta Wakaf
Perbedaan dalam memandang status harta benda wakaf terdapat dikalangan
ulama fikih. Menurut Imam Syafi‟i, wakaf adalah suatu ibadah yang di
syari‟atkan, wakaf berlaku sah bilamana Wakif telah menyatakan dengan
perkataan waqaftu (telah saya wakafkan), sekalipun tanpa diputuskan hakim.
Harta yang telah diwakabfkan menyebabkan waikf tidak memiliki hak
kepemilikan lagi, sebab kepemilikannya telah berpindah kepada Allah, dan juga
tidak menjadi milik dari penerima wakaf (Mauqf Alaih), akan tetapi wakif tetap
diperbolehkan mengambil manfaatnya.84
Menurut Ulama Syafi‟iyah, apabila wakaf telah dilaksanakan syarat dan
rukunnya, orang yang mewakafkan (wakif) tidak diperbolehkan meminjamkan,
memberikan, dan memperjual belikan.85
menurut Imam Hanafi wakaf adalah suatu
sedekah selama hakim belum mengumumkan bahwa harta itu adalah harta benda
wakaf, atau disyaratka denga ta‟lid sesudah meninggalnya orang yang berwakaf,
misalnya dikatakan “ bilamana saya telah meninggal, harta saya yang berupa
tanah ini saya wakafkan untuk kepentingan Madrasah Tsanawiyyah”, dengan
84
Abdul Ghafur Anshori, Hukum dan Praktik Perwakafan, hlm. 33.
85 Imam Suhadi, Wakaf Untuk Kesejahtraan Umat, hlm. 23.
58
Universitas Indonesia
demikian wakaf tanah untuk kepenbtingan Madrasah Tsanawiyyah baru berlaku
setelah Waqif meninggal dunia.86
Mazhab Maliki berpendapat bahwa esensi kepemilikan dari benda wakaf
tersebut tetap bebrada ditangan pemiliknya semula (waqif), akan tetapi wakif
sudah tidak diperkenankan menggunakannya lagi.87
pendapat ini diperkuat dengan
pendapatnya imam Hanafi, menurut Imam Hanafi harta benda wakaf itu tetap
menjadi milik Wakif oleh kerena itu pada suatu waktu harta wakaf tersebut dapat
diambil oleh Wakif atau Ahli Warisnnya Wakif setelah waktu yang ditentukan.88
2.8 Hakikat Harta Benda Wakaf
Salah satu unsur penting dalam wakaf adalah benda yang diwakafkan.
Tanpa benda wakaf maka wakaf tidak mungkin akan terealisasi. Benda wakaf
menurut fuqoha dan hukum positif dalam beberapa hal adalah sama, yaitu benda
wakaf itu bermanfaat dan bernilai ekonomis, salam arti sesuatu yang dapat
diperjual belikan, tahan lama, baik mendanya dan manfaatnya dan manfaat dapat
diambil oleh penerima wakaf.89
Menurut Mazhab Hanafi bahwa salah satu dari syarat benda yang dapat
diwakafkan itu adalah abadi atau kekal. Berdasarkan syarat ini maka segala harta
yang akan diwakafkan harus berupa harta yang kekal, agar dapat diabadikan
wakafnya. Oleh kerena itu ulama hanafiyah menetapkan dasar dari harta wakaf itu
adalah benda yang tidak bergerak, baik secara alami maupun rekayasa. Jika harta
benda wakaf itu berupa benda bergerak, maka wakafnya tidak sah.90
Dalam
Mazhab Hanafi dikenal kaidah: “pada prinsipnya, yang sah diwakafkan adalah
benda tidak bergerak”. Sumber kaidah ini adalah asas yang paling berpengaruh
terhadap wakaf, yaitu ta‟bid (tahan lama).91
86
Op.Cit, hlm. 34.
87 Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, Paradigma Baru Wakaf, hlm. 7
88 Abdul Ghafur Anshori, Hukum dan Praktik Perwakafan, hlm.34
89 Juhaya S. Praja, Perwakafan di Indonesia, hlm.57.
90 Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Hukum Wakaf, hlm.262.
91 Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, Fiqih Wakaf, hlm.31.
59
Universitas Indonesia
Menurut Abu Zahrah, mazhab Hanafi memperbolehkan wakaf benda
bergerak sebagai pengecualian dari prinsip jika memenuhu kondisi. Kondisi
tersebut adalah Pertama, benda bergerak itu selalu menyertai benda tetap. Hal
seperti ini ada dua yaitu karena hubungannya sangat erat dengan benda tetap,
seperti bangunan dan pepohonan dan sesuatu yang khusus disediakan untuk
kepentingan benda tetap, misalnya alat untuk membajak sawah. Kedua, boleh
mewakafkan benda bergerak berdasarkan atsar (perilaku) sahabat yang
memperbolehkan mewakafkan senjata, baju perang yang digunakan untuk
berperang. Ketiga, boleh mendatangkan pengetahuan dan merupakan sesuatu yang
bisa dilakukan berdasarkan Urf (tradisi). Seperti mewakafkan kitab-kitab dan
mushaf Al-Qur‟an. Menurut Mazhab Hanafi untuk mengganti benda wakaf yang
dikhawatirkan tidak kekal adalah memungkinkan kekalnya manfaat.
Para Ulama pengikut Mazhab Syafi‟i berpendapat bahwa dalam hal
mewakafkan harta dilihat dari kekekalan fungsinya atau manfaat dari harta
tersebut, baik barang bergerak, barang tidak bergerak maupun barang kongsi
(milik bersama). Menurut mazhab Maliki, boleh juga mewakafkan benda
bergerak, baik yang menempel dengan yang lain, baik ada nash yang
memperbolehkan nya atau tidak, karena mazhab ini tidak mensyaratkan
ta‟bid(harus selama-lamanya) pada wakaf. bahkan menurut Imam Maliki wakaf
itu sah meskipun sementara waktu.92
Sedangkan menurut Mazhab Hambali boleh mewakafkan harta, baik
bergerak maupun tidak seperti mewakafkan kendaraan, senjata untuk berperang,
hewan ternak dan kitab-kitab yang bermanfaat maupun mewakafkan benda-benda
yang tidak bergerak seperti tanah, tanaman, banginan dan sebagainya boleh
asalkan bermanfaat.
Kontrofersi tentang harta benda wakaf dikalangan fuqoha tersebut erat
kaitannya dengan konsep masing-masing mengenai harta benda (mal). Walaupun
definisi wakaf dan harta wakaf berbeda di kalangan fuqoha tetapi definisi wakaf
yang mereka kemukakan itu berpegang pada prinsip bahwa benda yang
diwakafkan pada hakikatnya adalah benda yang manfaatnya bersifat kekal.93
92
Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, Paradigma Baru Wakaf, hlm.41
93 Juhaya S. Praja, Perwakafan di Indonesia, hlm.57
60
Universitas Indonesia
Selain ulama Mazhab Hanafi, sebagian ulama mazhab Syafi‟i juga
memperbolehkan wakaf tunai (wakaf uang). Sebagaimana Abu Tsaur
meriwayatkan dari Imam Syafi‟I tentang diperbolehkannya wakaf tunai:
س اث صس ػ اشفؼ
جاص لفب ا اذبري
اذسا١“ Abu Tsauri meriwayatkan dari Imam Syafi‟I tentang dibolehkannya wakaf
dinar dan dirham (uang).94
Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memperbolehkan
wakaf tunai. Fatwa Komisi fatwa MUI tersebut dikeluarkan pada tanggal 11 Mei
2002. Argumentasi Ulama MUI tersebut dalam memperbolehkan wakaf uang
adalah Hadits Ibnu Umar :
Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra, dia berkata: Umar r.a telah berkata
kepada Nabi SAW, saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibar,
belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah
itu, saya bermaksud menyedekahkannya”. “Nabi SAW berkata “tahanlah
pokoknya dan sedekahkan buahnya pada Sabilillah. (H.R. al-Nasa‟i).
setelah itu Komisi Fatwa MUI merumuskan definisi baru tentang wakaf,
yaitu:
دجظ بي ميى االزفبع ث غ
ثمبء ػ١ ثمغغ ىف سلجز ػ
صشف جبح جد“menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya,
dengan cara tidak melakukan tindakan hokum pada benda tersebut (menjual,
memberikan atau mewariskannya), untuk disalurkan hasilnya pada sesuatu yang
mubah (tidak haram) yang ada”95
94
Al-Mawardi, Al-Hawi Al-Kabir, Tahqiq Dr. Muhammad Mathraji, Beirut: Dar-al Fikr, Jz
IX, 1994) hlm.379.
95 Fatwa Majelis Ulama Indonesia, ditandatangani tanggal 11 Mei 2002.
61
Universitas Indonesia
Momen besar perkembangan Wakaf Uang setelah adanya Fatwa dari MUI
adalah sejak Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang
Yudoyono, terpilih untuk yang kedua kalinya periode 2009-2014 barulah
mencanangkan Gerakan Nasional Wakaf Uang di Istana Negara, tepatnya tanggal
8 Januari 2010 setelah pelantikannya. Pencanangan ini sudah lama ditunggu
masyarakat ekonomi syariah Indonesia. Pencanangan Gerakan ini menjadi
tonggak sejarah dan momentum penting bagi gerakan wakaf produktif di
Indonesia dalam rangka meningkatan kesejahteraan umat dan bangsa Indonesia.96
Di Indonesia, isu wakaf uang mulai marak didiskusikan sejak awal tahun
2002, yaitu ketika IIIT (international Institute of IslamicThought) dan Departemen
Agama RI menggelar Workshop Internasional tentang Wakaf Produktif di
Batam, tgl 7-8 Januari 2002. Kemudian beberapa bulan pasca workshop itu, IAIN
Sumatra Utara menggelar Seminar Nasional Wakaf Produktif di Medan, pada
tangal 1-2 Mei 2002 dengan menghadirkan 16 pembiacara nasional. Setelah itu,
Seminar International tentang wakaf kembali digelar di Medan oleh Universitas
Islam Sumatera Utara, pada 6-7 Januari 2003 dengan menghadirkan pakar-pakar
wakaf berkaliber dunia, seperti Prof.Dr.Monzer Kahf, Prof.Dr.M/.A Mannan,
Prof.Dr.Sudin Haroun (Malaysia). Forum International Seminar Sumatera Utara
mementuk tim pembahas Rancangan Undang-Undang Waqaf, yang terdiri dari
Prof.Dr.Uswatun Hasanah, Dr.Mustafa Edwin, Nasution, Drs.Agustianto, M.Ag
dan beberapa dosen UISU.
Setelah beberapa momentum tersebut, isu wakaf produktif dan wakaf uang
menjadi marak dan banyak menjadi tema seminar di berbagai kampus dan
lembaga, seperti di Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Universitas
Prof.Dr.Hamka, UIN Jakarta, dan sebagainya. Hasil kajian yang panjang tersebut
kemudian membuahkan manfafat yang sangat menggembirakan, karena masalah
wakaf uang dimasukkan dan diatur dalam perundangan-undangan Indonesia
melalui UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Undang – Undang ini selanjutnya
disusul oleh kelahiran PP No No 42/2006. Dengan demikian, wakaf uang telah
96
http://pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1272:waka
f-uang-dan-peningkatan-kesejahteraan-umat&catid=8:kajian-ekonomi&Itemid=60, Wakaf Uang
dan Peningkatan kesejahteraan umat, diakses tanggal 9 Juli 2014.
62
Universitas Indonesia
diakui dalam hukum positif di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Republik
Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf diarahkan untuk memberdayakan
wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial
ekonomi umat Islam. Kehadiran Undang-undang wakaf ini menjadi momentum
pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman
yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara
modern.
Dalam perundang-undangan sebelumnya, PP No.28 tahun 1977 tentang
Perwakafan Tanah Milik, konsep wakaf identik dengan tanah milik, maka dalam
Undang-Undang Wakaf yang baru ini konsep wakaf mengandug dimensi yang
sangat luas. Ia mencakup harta tidak bergerak maupun yang bergerak, termasuk
wakaf tunai yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian
tempat ibadah dan sosial keagamaan. Formulasi hukum yang demikian, jelas suatu
perubahan yang sangat revolusioner dan jika dapat direalisasikan akan memiliki
akibat yang berlipat ganda atau multiplier effect, terutama dalam kaitannya
dengan pemberdayaan ekonomi umat Islam.
Umat Islam Indonesia selama ratusan tahun sudah terlanjur
mengidentikkan wakaf dalam bentuk tanah, dan benda bergerak yang sifat
bendanya tahan lama. Dengan demikian, UU No. 41 tahun 2004 diproyeksikan
sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering), melakukan perubahan-
perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar sesuai dengan semangat
UU tersebut. Salah satu regulasi baru dalam Undang-Undang Wakaf tersebut
adalah Wakaf Tunai.
Di lihat dari tujuan dan kontribusi yang dapat diberikan oleh institusi
wakaf uang , maka keberadaan wakaf uang di Indonesia menjadi sangat krusial.
Setidaknya ada beberapa hal yang mengakibatkan pentingnya pemberdayaan
wakaf di Indonesia:97
1. Angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi, yang perlu mendapat perhatian
dan langkah-langkah yang konkrit.
2. Kesenjangan yang tinggi antara penduduk kaya dengan penduduk miskin
97
Ibid
63
Universitas Indonesia
3. Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim yang besar, sehingga wakaf
memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan
4. Sejumlah bencana yang terjadi, mengakibatkan terjadinya defisit APBN,
sehingga diperlukan kemandirian masyarakat dalam pengadaan public goods.
Di Indonesia, lembaga pengelola wakaf nasional adalah Badan Wakaf
Indonesia (BWI). Selain itu lembaga-lembaga wakaf lainnya yang dikelola
masyarakat dan ormas Islam juga sudah banyak yang muncul, Salah satunya
adalah Waqf Fund Management dan Tabung Wakaf Indonesia (TWI). Dengan
adanya lembaga yang concern dalam mengelola wakaf uang , maka diharapkan
kontribusi dalam mengatasi problem kemiskinan dan kebodohan yang mendera
bangsa akan lebih signifikan. Apalagi sebagaimana yang telah dihitung oleh
seorang ekonom, Mustafa E. Nasution, Ph.D, potensi wakaf tunai umat Islam di
Indonesia saat ini bisa mencapai Rp 3 triliun setiap tahunnya. Bahkan bisa jauh
lebih besar dari itu.
61
BAB 3
TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN SYARI’AH
3.1 Sejarah Kelahiran Bank Islam
3.1.1 Sejarah Kelahiran Bank
Lahirnya bank pada mulanya adalah hasil dari perkembangan cara
penyimpanan harta benda. Para saudagar merasa khawatir membawa perhiasan
dan lain sebagainya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya sedangkan
pencuri dan perampok serta kejahatan yang lainnya senantiasa mengancam. Bank
merupakan tempat yang dipercayai mampu menjaga karena memiliki kekuatan
dalam penjagaan dan birokrasi administrasi yang rapi. Masyarakat umum mulai
tertarik dan menggunakan jasa-jasanya. Sejak saat itulah bank mulai berkembang
dengan cara-caranya yang berbeda-beda.1
Bank memberi jaminan atas penyimpanan dan penyimpanpun dapat
mempergunakan uang para penyimpannya dengan mempergunakan cek, syarat
wesel dan lain sebagainya. Bank yang paling pertama berdiri berada di Venesia
dan Genoa di Italia, sekitar abad ke 14. Kota-kota tersebut dikenal dengan kota-
kota dagang. Manusia dagang ke kota ini dari berbagai tempat untuk tukar
menukar barang dagangannya. Dari dua kota ini kemudian sistem bank tersebut
berpindhah sistem ke Eropa Barat.2
Pada zaman pra Islam sebenarnya telah ada bentuk-bentuk perdagangan
yang sekarang telah dikembangkan di dunia bisnis modern. Bentuk-bentuk itu
misalnya al-musyarakah (joint venture), al-bai’u takjiri (venture capital), al-
Ijarah (leasing), attakaful (insurance), al-bai’u bitsamanil ajil (instalmen
1 Lihat Rahmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syari’ah di Indonesia, Jakarta: sinar
grafika, Cet.1 2012, hlm.1
2 Fuad Mohd Fachruddin, 1983, Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi
Bandung: PT: Alma‟arif, hlm. 110-111
62
Universitas Indonesia
sale),murabahah, pinjam dengan tambahan bunga (riba) dan lain-lain. Bentuk
perdagangan tersebut telah berkembang di jazirah arab, yang letaknya sangat
strategis bagi perdagangan saat itu, khususnya di kota mekah, jedah dan madinah
jazirah arab. Perdagangan antara Asia-Afrika-Eropa pada saat itu sangat
dipengaruhi oleh bentuk-bentuk ekonomi mesir purba, yunani kuno dan romawi
sekitar 2500 tahun sebelum masehi telah mengenal sistem perbankan. Demikian
juga Babilonia yang sekarang menjadi wilayah irak juga mengenal sistem
perbankan sekitar 2000 tahun sebelum masehi.3Ini berarti sebelum masehi sistem
perbankan telah berkembang dan telah diperlukan oleh umat manusia dalam
mengatur sistem pembiayaan dan pembayaran. Dan bank-bank itupun telah
dilarang untuk membungakan uang yang dikenal dengan istilah Riba.4
3.1.2 Sejarah Bank Pada Masa Rasulullah SAW
Pada zaman rasulullah dan para sahabat, terdapat individu-individu yang
telah melaksanakan fungsi perbankan, meskipun individu-individu tersebut tidak
melaksanakan seluruh fungsi perbankan. Ada para sahabat yang melaksanakan
fungsi menerima titipan harta, ada juga para sahabat yang melaksanakan fungsi
pinjam-meminjam uang, ada yang melaksanakan fungsi pengiriman uang, dan
ada pula yang memberikan modal kerja. Oleh karena itu sebenarnya praktik
perbankan telah lazim dilaksanakan pada masa Rasulullah, walaupun fungsinya
itu masih belum menyatu menjadi satu lembaga seperti bank-bank yang ada pada
saat ini.5
Barulah pada masa Bani Abbasiyah ketiga fungsi perbankan di lakukan
oleh satu individu. Perbankan mulai berkembang pesat ketika beredar banyak
jenis mata uang pada masa itu, sehingga perlu keahlian khusus untuk
membedakan antara satu mata uang dengan mata uang lainnya. Hal ini diperlukan
karena setiap mata uang memiliki kandungan logam mulia yang berbeda-beda.
Sehingga mempunyai nilai yang berbeda juga. Orang yang mempunyai keahlian
3 Warkum sumitro, 1996, Asas-asas perbankan Islam dan lembaga-lembaga terkait (BMUI
& Takaful) di Indonesia, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hlm.6
4 Rahmadi Usman, Op.Cit., hlm.2
5 Ibid
63
Universitas Indonesia
khusus untuk membedakan kandungan logam mulia yang terdapat pada mata uang
itu disebuht naqid, sarraf dan jihbiz.6Aktivitas ekonomi ini merupakan cikal bakal
dari praktik penukaran mata uang (Money Changer) yang kita kenal saat ini.7
Istilah jihbiz sendiri mulai dikenal sejak zaman khalifah Mu’awiyah (661-680M)
yang pada saat itu istilah jihbiz diambil dari bahasa persia yaitu Kahbad atau
Kihbud.
Peran bankir pada zaman Abbasiyah mulai populer pada pemerintahan
khalifah Muqtadir (908-932M), pada saat pemerintahan tersebut setiap wazir
(menteri) memiliki bankir sendiri. Pada masa pemerintahan Muqtadir ini praktik
perbankan ditandai dengan beredarnya saq (cek) yang sudah meluas ke beberapa
daerah sebagai media pembayaran. Bahkan peranan dari bankir telah meliputi tiga
aspek, yaitu pertama, menerima deposit, kedua, menyalurkannya, dan ketiga
mentransfer uang. Pada fungsi yang ketiga ini uang telah dapat ditransfer dari satu
negeri ke negeri yang lain tanpa harus memindahkan fisik uang tersebut.
3.1.3 Munculnya Gagasan Bank Islam:
Kelahiran Bank Islam tidak terlepas dari upaya penggalangan dana
masyarakat yang selaras dengan orientasi nilai yang tumbuh dalam masyarakat
Islam. Islam melarang praktik mu‟amalah yang mengandung unsur riba, sehingga
perlu didirikan bank tanpa bunga yang sesuai dengan prinsip dasar ajaran Islam.
Sebagian besar Ulama beranggapan bahwa bunga bank itu riba,seperti pendapat
dari beberapa ulama berikut ini:
a. Abu zahrah, Abu „ala al-Maududi Abdullah al-„Arabi dan Yusuf Qardhawi
mengatakan bahwa bunga bank itu termasuk riba nasiah yang dilarang
oleh Islam. Karena itu umat Islam tidak boleh bermuamalah dengan bank
yang memakai system bunga, kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa.
Bahkan menurut Yusuf Qardhawi tidak mengenal istilah darurat atau
terpaksa, tetapi secara mutlak beliau mengharamkannya. Pendapat ini
dikuatkan oleh Al-Syirbashi, menurutnya bahwa bunga bank yang
6 Adiwarman A. Karim, Bank-bank Islam: Analisis Fiqh dan keuangan, Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada,2004 hlm. 20
7 Ibid., hlm. 21
64
Universitas Indonesia
diperoleh seseorang yang menyimpan uang di bank termasuk jenis riba,
baik sedikit maupun banyak. Namun yang terpaksa, maka agama itu
membolehkan meminjam uang di bank itu dengan bunga.
b. Dr. Sayid Thantawi yang berfatwa tentang bolehnya sertifikat obligasi yang
dikeluarkan Bank Nasional Mesir yang secara total masih menggunakan
sistem bunga, dan ahli lain seperti Dr. Ibrahim Abdullah an-Nashir dalam
buku Sikap Syariah Islam terhadap Perbankan mengatakan, “Perkataan yang
benar bahwa tidak mungkin ada kekuatan Islam tanpa ditopang dengan
kekuatan perekonomian, dan tidak ada kekuatan perekonomian tanpa ditopang
perbankan, sedangkan tidak ada perbankan tanpa riba. Ia juga mengatakan,
“Sistem ekonomi perbankan ini memiliki perbedaan yang jelas dengan amal-
amal ribawi yang dilarang Al-Qur‟an yang Mulia. Karena bunga bank adalah
muamalah baru, yang hukumnya tidak tunduk terhadap nash-nash yang pasti
yang terdapat dalam Al-Qur‟an tentang pengharaman riba
c. Menurut musyawarah nasional alim ulama NU pada 1992 di Lampung, para
ulama NU tidak memutus hukum bunga bank haram mutlak. Memang ada
beberapa ulama yang mengharamkan, tetapi ada juga yang membolehkan
karena alasan darurat dan alasan-alasan lain.
d. Pendapat A. Hasan, pendiri dan pemimpin Pesantren Bangil (Persis)
berpendapat bahwa bunga bank seperti di negara kita ini bukan riba yang
diharamkan, karena tidak bersifat ganda sebagaimana yang dinyatakan dalam
surat Ali Imran ayat 130.
e. Hasil rapat komisi VI dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-27 Tarjih dan
Tajdid Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)
menetapkan, bunga perbankan termasuk riba sehingga diharamkan.
f. Pertemuan 150 Ulama‟ terkemuka dalam konferensi Penelitian Islam di bulan
Muharram 1385 H, atau Mei 1965 di Kairo, Mesir menyepakati secara
aklamasi bahwa segala keuntungan atas berbagai macam pinjaman semua
merupakan praktek riba yang diharamkan termasuk bunga bank. Berbagai
65
Universitas Indonesia
forum ulama internasional yang juga mengeluarkan fatwa pengharaman bunga
bank.8
Oleh karena itu hukumnya bunga bank adalah haram. Sehingga perlu diusahakan
adanya sistim perbankan yang dalam operasinya tidak mengenakan bunga kepada
nasabahnya (interest fee banking system) atau lazim disebut dengan perbankan
syari‟ah.
Perbankan yang bebas dari bunga merupakan konsep gagasan yang relatif
baru. Gagasan untuk mendirikan bank Islam itu lahir sejak belum adanya kesatuan
pendapat dikalangan Islam sendiri mengenai apakah bunga yang dipungut oleh
bank konvensional maupun tradisional merupakan sesuatu yang haram atau halal.
Mereka yang berpendapat bahwa bunga yang dipungut oleh bank konvensional
maupun tradisional merupakan riba yang dilarang oleh agama Islam berkeinginan
membangun suatu lembaga-lembaga yang dapat memberikan jasa-jasa
penyimpanan dana dan pemberian fasilitas pembiayaan yang tidak berdasarkan
bunga dan beroperasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari‟at Islam, karena
mereka berpendapat bahwa bank merupakan sesuatu yang telah menjadi
kebutuhan masyarakat saat ini.9
Konsep teoritis tentang bank Islam telah muncul pada tahun 1940-an,
namun belum dapat diwujudkan. Belum dapat terwujudnya bank Islam saat itu
karena kondisinya belum memungkinkan dan juga belum ada pemikiran tentang
konsep bank Islam yang meyakinkan. Penulis yang mula-mula menyampaikan
gagasan tentang konsep bank Islam yang berdasarkan atas Profit Sharing yaitu
Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948) dan Mahmud Ahmad (1952).
Kemudian uraian yang lebih terperinci lagi tentang gagasan tersebut ditulis oleh
Mawdudi (1950).10
Barulah pada tahun 1969, secara kolektif di tingkat Internasional muncul
gagasan untuk mendirikan Bank Islam dalam konferensi negara-negara Islam
8 http://hukum-islam.com/2013/03/hukum-bunga-bank-dalam-islam/, Hukum Bunga bank
dalam Islam, diakses pada tanggal 8 juni 2014.
9 Lihat Sutan Remy Sjahdeini, 1999, Perbankan Islam dan kedudukannya dalam tatahukum
Perbankan Indonesia, Jakarta: Puastama Utama Grafiti, hlm. 4
10 Rahmadi Usman, Op.Cit., hlm.5
66
Universitas Indonesia
sedunia yang diselenggarakan dari tanggal 21-27 april 1969 di Kuala Lumpur
Malaysia yang diikuti 19 negara peserta dan 6 negara sebagai peninjau.
Konferensi tersebut membahas soal riba dan soal bank, yang kemudian
menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut:
1. Tiap keuntungan haruslah tunduk kepada hukum untung dan rugi, kalau
tidak ia termasuk riba. Dan untuk Riba baik sedikit maupun banyak
hukumnya adalah sama-sama haram
2. Diusulkan supaya terbentuk suatu bank yang bersih dari sistem riba dalam
waktu secepat mungkin, dan
3. Sementara sambil menunggu berdirinya bank Islam tersebut, bank-bank
yang menerapkan sistem bunga diperbolehkan tetap beroprasi, namun jika
benar-benar dalam keadaan darurat.11
Secara Internasional perkembangan bank Islam pertamakali di prakarsai
oleh Mesir. Pada sidang Menteri Luarnegeri Organisasi Negara-Negara
Konferensi Islam (OKI) di Karachi, Pakistan bulan Desember 1970. Mesir
mengajukan proposal tentang pendirian Bank Islam Internasional untuk
perdagangan dan pembangunan (International Islamic Bank for Trade and
Development) dan Proposal pendirian Federasi Bank Islam (Federation of Islamic
Banks). Inti usulan dalam proposal tersebut adalah bahwa suatu sistem keuangan
dengan bunga harus digantikan dengan suatu sistem kerjasama dengan skema bagi
hasil keuntungan maupun kerugian. Proposal tersebut diterima dan sidang
menyetujui rencana pendirian bank Islam Internasional dan Federasi Bank Islam.
Semula pembentukan bank Islam banyak diragukan karena beberapa
alasan, yaitu pertama,banyak yang beranggapan bahwa sistem perbankan yang
bebas bunga (interest fee) adaah suatu sistem yang tidak mungkin dan tidak lazim,
kedua: banyak yang mempertanyakan bagaimana nanti bank Islam itu akan
membiayai operasinya.12
Seiring dengan perkembangan politik negara-negara
Islam tersebut, pada tahun 1970-an mulai bermunculan lembaga keuangan yang
berdasarkan prinsip syari‟ah, mendekati awal tahun 1980-an bank bank Islam
11
Warkum Sumitro, Op.Cit., hlm 8 dan Fuad Mohd. Fakhruddin, Op.Cit., Hlm.103
12 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 1994, Enseclopedi Islam jilid 1, Jakarta: PT Ichatiar
Baru Van Hoeve, hlm. 233.
67
Universitas Indonesia
telah bermunculan di Mesir, Sudan, Negara-negara Teluk, Pakistan, Iran,
Malaysia, Bangladesh dan Turki.
Perkembangan Bank Islam untuk selanjutnya menjadi luas lagi, beberapa
bank konvensional di barat justru membuka layanan syari‟ah melalui Islamic
window. setelah melihat keunggulan dari sistem perbankan Islam dan besarnya
prospek pengembangan bank syari‟ah tersebut. Tercatat pada tahun 2005,
Deutsche Bank, HSBC, Citigroup dan BNP Paribas yang mengikuti mendirikan
Unit Layanan Syari‟ah. Sejak saat itu perkembangan perbankan syari‟ah tidak
hanya dijalankan secara murni melainkan pada beberapa bank menerapkan Dual
Banking System.perbankan Konvensional juga membuka ruang bagi
pengembangan Perbankan Syari‟ah dengan mekanisme Islamic Window. Pada
perjalanannya sistem perbankan berbasis syari‟ah semakin hari semakin populer
bukan hanya dikalangan negara-negara Islam saja melainkan negara-negara barat.
Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya bank-bank yang menerapkan konsep
syari‟ah di barat dengan konsep dual banking system.
3.2 Dasar Hukum Bank Syari’ah
Islam mengajak kepada pemilik harta untuk mengembangkan harta milik
mereka dan menginvestasikannya, sebaliknya melarang mereka untuk
membekukan dan tidak memfungsikannya. Demikian juga tidak diperbolehkan
bagi pemilik uang untuk menimbun dan menahannya dari peredaran sedangkan
orang lain (umat) dalam keadaan membutuhkan untuk menggunakan uang itu
untuk mengerjakan proyek-proyek yang bermanfaat dan membawa dampak pada
terbukannya lapangan kerja bagi para pengangguran dan menggairahkan aktivitas
perekonomian. Sehingga al-Qur‟an dalam hal ini memberi peringatan kepada
orang-orang yang menyimpan harta dan yang bersikap egois dengan ancaman
yang berat. Sebagaimana Allah berfirman dalam al-Qur‟an surat at-Taubah ayat
34-35.
68
Universitas Indonesia
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari
orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta
orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan
Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak
menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa
mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu
dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan
punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang
kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa
yang kamu simpan itu."13
Kemudian al-Qur‟an surat Ali Imran ayat 130:
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan
berlipat ganda[228]14
dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat
keberuntungan.
Kemudian al-Qur‟an surat Ar-Ruum ayat 39
Artinya: Sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar pada harta manusia
bertambah, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu
berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah,
13
Departemen Agama Rebublik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, Jakarta. 2008
14 Yang dimaksud Riba di sini ialah Riba nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa
Riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasiah
dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan.
Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak
jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas
dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah
yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.
69
Universitas Indonesia
Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan
(pahalanya).
Ayat-ayat tentang riba di atas, turun secara bertahap (gradual) yang
disesuaikan dengan situasi dan kondisi umat Islam pada masa itu. Ayat tentang
riba yang pertama turun melalui surat ar-Ruum ayat: 39 pada periode Makkah.
Ayat tersebut tidak secara jelas atau konkrit melarang atau mengharamkan riba,
tetapi ayat tersebut baru menjelaskan bahwa riba(tambahan dari pinjaman atau
jual-beli)itu tidak mendatangkan pahala disisi Allah. Hal ini berbeda dengan
zakat, yang mendatangkan nilai pahala disisi Allah, yakni berlipatgandanya
pahala akan datang dari Allah karena zakat, jika hal itu dilakukan.
Kemudian pada periode Madinah secara tegas Allah S.W.T
mengharamkan atau melarang riba tersebut. Sehingga turunlah surat an-Nisa’ ayat
160-161 yang menjelaskan tentang hukuman yang akan diterima oleh orang yang
selalu memakan harta riba tersebut, yaitu disamakan dengan orang kafir yang
akan mendapatkan siksa yang amat pedih dari Allah. Setelah itu turunlah surat Ali
Imran ayat 130 yang secara jelas mengharamkan atau melarang memakan harta
yang didapat dari riba, kemudian dilanjutkan dengan larangan yang terakhir yaitu
surat al-Baqarah ayat 278-280, yang juga mengharamkan atau melarang umat
Islam untuk mengerjakan segala macam perbuatan riba dalam berbagai bentuk.
Namun dari ayat tersebut juga ditekankan jika orang tersebut telah melakukan
perbuatan riba hendaknya bertaubat dengan tidak melakukannya lagi, maka
hartanya tidak akan diganggu dan tidak akan menganiaya orang lain.
Sebagaimana yang dimaksud dalam surah al-Baqarah ayat 278-279,
pelarangan bunga dalam Islam dimaksudkan untuk menciptakan sebuah sistem
ekonomi dimana segala bentuk eksploitasi atau penganiayaan harus ditiadakan.
Islam menghendaki keadilan antara pihak pemodal dengan pengusaha, dimana
pemodal tidak boleh dijanjikan akan menerima imbalan hasil tanpa melakukan
apa-apa atau menanggung resiko bersama.15
Selanjutnya larangan tentang riba ini juga dipertegas lebih lanjut dalam
beberapa hadis Nabi Muhammad S.A.W . ada hadis yang memperjelas
15
Muhammad Nadratuzzaman hosen dan Sunarwin Kartika Setiati, 2008, Tuntutan Praktis
Menggunakan Jasa Perbankan Syari’ah, Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syari‟ah (pkes
publishing), hlm 17.
70
Universitas Indonesia
pengharaman atau pelarangan riba yang telah di atur didalam Al-Qur‟an, juga ada
hadis yang memperluas atau menambah kegiatan mu’amalah atau perniagaan
yang dikatagorikan sebagai riba dalam berbagai bentuk. Pada dasarnya hadis-
hadis tersebut memepertegas pengharaman atau pelarangan riba dalam berbagai
bentuk dengan disertai ancaman (hukuman) masuk neraka bagi mereka yang
melakukannya. Hadis-hadis yang mengharamkan atau melarang praktik-praktik
riba dalam perniagaan umat Islam yaitu sebagai berikut:
1. Hadis Riwayat Bukhari Nomor 2084 dalam kitab al-Buyu’:
Diriwayatkan oleh Aun bin Abi Juhaifa, “ Ayahku membeli seorang budak
yang pekerjaannya membekam (mengeluarkan darah kotor dari kepala),
ayahku kemudian memusnahkan peralatan si budak tersebut. Aku bertanya
kepada ayah mengapa beliau melakukannya, ayahku menjawab bahwa
Rasulullah SAW melarang untuk menerima uang dari transaksi darh, anjing,
dan kasab budak perempuan, beliau juga melaknat pekerjaan pentato dan yang
minta di tato, menerima dan memberi riba serta beliau melaknat para pembuat
gambar.16
2. Hadis Riwayat Bukhori Nomor 2145 dalam kitab al-Wakalah:
Diriwayatkan oleh Abu Sa‟id Al-Khudri bahwa suatu ketika bilal membawa
Barni(sejenis kurma berkualitas baik) ke hadapan Nabi dan Nabi bertanya
kepada Sahabat Bilal “Darimana engkau mendapatkannya?” bilal menjawab,
“saya mempunyai sejumlah kurma dari jenis yang rendah mutunya dan
menukarkannya dua sha‟ untuk satu sha‟ kurma jenis Banrni untuk dimkan
oleh Nabi, slepas itu nabi terus berkata, Hati hati! Hati-hati! Ini sesungguhn6ya
riba, ini sesungguhnya riba. Jangan berbuat begini, tetapi jika kamu membeli
kurma yang mtunya lebih tinggi juallah kurma yang mutunya rendah untuk
mendapatkan uang dan kemudian gunakanlah uang tersebt untuk membeli
kurma yang bermutu tinggi itu.17
3. Hadis Riwayat bukhori Nomor: 2034 dalam kitab al-Buyu’
Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abu Bakr bahwa ayahnya berkata: nabi
melarang penjualan emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali sama
beratnya, dan membolehkan kita menjual emas dengan perak dan begitu pula
sebaliknya.18
4. Hadis riwayat Muslim Nomor 2971 dalam kitab al-Masaqqh:
16
Zainuddin Ali, 2008 Hukum Perbankan Syari’ah Jakarta : CV Sinar Grafika, hlm. 103
17 Ibid, hlm. 104
18 Ibid
71
Universitas Indonesia
Diriwayatkan oleh Ab Sa‟id al Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda “emas
hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum,
tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam,
pembayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi
tambahan atau meminta tambahan sesungguhnya ia telah berurusan dengan
riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah.19
5. Hadis Riwayat Bukhari Nomor 6525 dalam kitab at-Ta’bir:
Diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah bersabda “malam
tadi aku bermimpi, telah datang dua orang dan membawaku ke Tanah Suci.
Dalam perjalanan sampailah kami ke Sungai Darah dimana didalamnya berdiri
seorang laki-laki. Dipinggir sungai tersebut berdiri seorang laki-laki dengan
batu ditangannya. Laki-laki yang berada di tengah sungai itu berusaha untuk
keluar tetapi laki-laki yang dipinggir tadi melempari mulutnya dengan batu dan
memaksanya kembali ke tempat asal. Aku bertanya “siapakah itu?” Aku diberi
tahu bahwa laki-laki yang barada ditengah sungai itu adalah orang yang
memakan riba”20
6. Hadis Riwayat Muslim Nomor 2995 dalam Al-Kitab al-Musaqqah:
Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerima riba,
orang yang membayarnya dan orang yang mencatatnya dan dua orang
saksinya, kemudian beliau bersabda “Mereka itu semuanya sama.21
7. Amanat Nabi SAW pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah yang
menekankan sikap ajaran agama Islam tentang larangan riba sebagai berikut:
Ingatlah bahwa kamu akan menghadap tuhanmu, dan Dia pasti akan
menghitung amalmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba, oleh karena
itu utang akibat riba harus dihapuskan. Modal (Uang Pokok) kamu adalah hak
kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidak adilan.22
Sementara itu dikalangan cendikiawan muslim sendiri sebenarnya terjadi
perbedaan pendapat dalam hal menanggapi pengambilan riba (tambahan dari
pinjaman atau jual beli). Ada yang secara tegas mengharamkan pengambilan riba
19
Ibid
20 Ibid., hlm. 105
21 Ibid.
22 Ibid., hlm. 106
72
Universitas Indonesia
itu, sementara yang lain ada yang menghalalkan asal dalam keadaan darurat dan
tidak menimbulkan kesengsaraan bagi pihak lainnya.23
Abu Zahrah, Abdul A‟la al Mauddi dan Muhammad Abdullah al-Arabi
menyebutkan “bunga” bank itu riba Nasi’ah yang dilarang oleh Islam. Oleh
karena itu umat muslim tidak boleh bermu’amalah dengan bank yang memakai
sistim bunga, kecuali bila dalam keadaan darurat atau terpaksa. Mereka juga
mengharapkan lahirnya bank Islam yang tidak memakai sistem bunga
samasekali.24
Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu’ menyatakan bahwa al-Mawardi
berkata: sahabat-sahabat kami (Ulama Mazhab Syafi‟i) berbeda tentang
pengharaman riba yang ditegaskan oleh al-Qur‟an atas dua pandangan yaitu:
1. Pengharaman tersebut bersifat mujmal (global) yang dijelaskan oleh
sunnah. Setiap hukum tentang riba yang di jelaskan oleh sunnah adalah
merupakan penjelasan (bayan) terhadap ke-Mujmalan al-Qur‟an, baik riba
naqd (tunai) maupun riba nasi’ah.
2. Bahwa riba yang ada didalam al-Qur‟an sesungguhnya adalah riba nas’ah
yang dikenal oleh masyarakat jahiliyah dan permintaan atas harta
tambahan atas harta (piutang) penambahan masa (pelunasan). Salah
seorang diantara mereka apabila jatuh tempo pembayaran piutangnya dan
pihak yang berutang tidak membayarnya, ia menambahkan piutangnya dan
menambahkan pula masa pembayarannya. Hal seperti itu akan dilakukan
lagi pada masa jatuh tempo masa berikutnya. Itulah yang dimaksud dalam
firman Allah dalam Al-Qur‟an:
“janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda....” kemudian
sunnah juga menambahkan riba yang dilarang yaitu riba dalam bentuk
pertukaran mata uang (naqad) terhadap bentuk riba yang terdapat dalam
al-Qur‟an. Bunga Uang atas pinjaman (qardh) yang berlaku diatas lebih
buruk daripada riba yang telah diharamkan leh Allah dalam Al-Qur‟an.
Karena dalam riba, tambahan hanya dikenakan pada saat jatuh tempo,
23
Rahmadi Usman Op.Cit., hlm. 28
24 Masjfuk Zuhdi, 1997, Masa‟il Fiqhiyyah, Jakarta: Toko Gunung Agung hlm.112
73
Universitas Indonesia
sedangkan dalam sistim bunga tambahan sudah dikenakan sejak terjadi
transaksi.
Keputusan majelis tarjih Muhamadiyah tahun 1968 di Sidoarjo
memutuskan bahwa bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank
tanpa riba hukumnya halal. Bunga bank yang diberikan oleh bank-bank
milik negara yang diberikan kepada nasabahnya atau sebaliknya, termasuk
perkara musytabihat atau syubhat, artinya tidak jelas atau masih
meragukan.
Istilah bank memang tidak dikenal dalam khasanah keilmuan Islam, yang
dikenal adalah bahasa Jihbiz. Kata “jihbiz” berasal dari bahasa persia yang berarti
penagih pajak. Istilah jihbiz mulai dikenal pada zaman Mu‟awiyah yang pada saat
itu fungsinya sebagai penagih pajak dan penghitungan barang atas barang dan
tanah. Di zaman Bani Abbasiyah, jihbiz populer sebagai suatu profesi jenis baru
yang disebut fulus yang terbuat dari tembaga. Sebelumnya uang yang di gunakan
adalah dinar (terbuat dari emas) dan dirham (terbuat dari perak). Dengan
munculnya fulus ini timbul kecenderungan dikalangan para gubernur untuk
mencetak fulusnya masing-masing, sehingga beredar banyak sekali fulus dengan
nilai yang berbeda-beda. Keadaan inilah yang kemudian mendorong munculnya
profesi baru yaitu penukaran uang. Pada zaman itu jihbiz tidak hanya melakukan
penukaran uang tetapi menerima titipan dana, meminjamkan uang dan meerima
jasa pengiriman uang. Pada bani abbasiyah tersebut ketiga fungsi utama
perbankan tersebut oleh jihbiz secara individu.25
Di dalam al-Qur‟an dan al-Hadits memang tidak diterangkan dengan jelas
tentang perbankan atau jihbiz, sehingga timbul pertanyaan “apakah hal tersebut
boleh dilaksanakan?”,untuk mengetahui tentang jawaban pertanyaan tersebut kita
kembalikan kepada kaidah fiqhiyyah
25
http://aljurem.wordpress.com/2012/01/31/dasar-hukum-dan-pengertian-perbankan-
syariah. Dasar Hukum dan Pengertian Perbankan Syari‟ah, diakses tanggal 06 juni 2014.
74
Universitas Indonesia
االصل ىف املعامالت االباحة حىت
”مىجىد دليل على حترمها "
Artinya: hukum dari segala sesuatu tentang mu‟amalat pada dasarnya adalah
diperbolehkan kecuali jika ada dalil yng melarangnya.
Sehingga segala transaksi baru muncul dimana belum dikenal sebelumnya
oleh hukum Islam, maka transaksi tersebut dapat diterima kecuali terdapat
implikasi dari dalil al-Qur‟an dan al-Hadits yang melarangnya secara eksplsit
maupun implisit. Begitu pula dalam menyikapi perbankan atau jihbiz, pada
dasarnya ketiga fungsi perbankan boleh dilakukan kecuali bila dalam
melaksanakan fungsinya bank melakukan usahanya yang dilarang oleh syari‟at.
Bila kita lihat saat ini bank-bank konvensional yang dilakukan dengan fungsi
bunga, maka bunga tersebutlah yang dilarang oleh agama.
3.2.1 Dasar hukum bank syari’ah di Indonesia
Bank syari‟ah di Indonesia mendapatkan dasar pendirian yang kokoh
setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Hal ini karena sejak
saat itu diberikan keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk nol persen
(peniadaan bunga sekaligus). Perbankan syari‟ah di Indonesia diawali dari aspirasi
masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim untuk memiliki sebuah alternatif
sistim perbankan yang Islami. Selain itu masyarakat meyakini bahwa sistem
pebankan syari‟ah yang menerapkan bagi hasil sangat menguntungkan baik untuk
nasabah maupun bank itu sendiri.
Pada awal tahun 1980-an, rintisan pendirian perbankan syari‟ah mulai
dilakukan. Maraknya seminar dan diskusi tentang urgensi bank syari‟ah yang
telah dilakukan masyarakat dan akademisi semakin gencar. Sebagai sebuah uji
cobanya mereka mempraktikkan gagasan ujicobanya yaitu menggagas bank
syari‟ah dalam skala kecil. Pada saat itu berdirilah Bait Al-Tamwil Salman di
Institut Teknologi Bandung dan koperasi Ridho Gusti di Jakarta. Para tokoh yang
75
Universitas Indonesia
terlibat dalam kajian itu adalah Karnen A. Perwaatmaja, M. Dawam Rahardjo,
A.M. Saifuddin, M. Amin aziz dan lain-lain.26
Mencermati aspirasi masyarakat untuk memiliki lembaga keuangan
syari‟ah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) selanjutnya menindaklanjuti aspirasi
tersebut dengan melakukan pendalaman konsep-konsep keuangan syari‟ah,
termasuk sistem perbankan syari‟ah. Pada tanggal 18-20 Agustus 1990 tepatnya di
Cisarua Bogor MUI menyelenggarakan lokakarya Bunga Bank dan Perbankan
yang hasil daripada lokakarya terseut kemudian dibahas lebih mendalam oleh
MUI dalam MUNAS ke -4 pada tanggal 22-25 Agustus 1990 yang menghasilkan
lahirnya amanat untuk mendirikan Bank Islam pertama di Indonesia sehingga
berdirilah PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI).
Dukungan dalam mengembangkan sistem perbankan syari‟ah ini
selanjutnya terlihat dengan dikeluarkannya perangkat hukum yang mendukung
sistem operasional bank syari‟ah yaitu Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang
perbankan dan PP No. 72 tahun 1992 dan ketentuan ini menandai dimulainya era
sistem perbankan ganda (dual banking system) di indonesia yaitu sistem
perbankan konvensional dan sistem perbankan bagi hasil.27
Untuk lebih-jelasnya
peraturan yang mendukung perbankan syari‟ah mulai dari berdirinya hingga saat
ini secara berturut-turut dapat kami rinci sebagai berikut:
3.2.2 Peraturan Hukum Terkait Dengan Bank Syariah di Indonesia
1. UU No.7 Tahun 1992
Sejak diberlakukannya UU No.7 Tahun 1992, yang memosisikan bank Syariah
sebagai bank umum dan bank perkreditan rakyat, memberikan angin segar
kepada sebagian umat muslim yang anti-riba, yang ditandai dengan mulai
beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Mei 1992
dengan modal awal Rp.106.126.382.000,00.
26
M. Amin aziz, Mengembangkan Bank Islam Di Indonesia (jakarta: Bankit, 1992).
27 Makalah pelatihan perbankan syari‟ah 18-19 April 2000, di Muamalat Institute,
dilaksanaka oleh Divisi Kajian Akuntansi dan Manajemen Islam (KAMI) FSI SM-FEUI
bekerjasama dengan Muharram in Cares and Retrospection (Macro 1421 H).
76
Universitas Indonesia
Namun bukan hanya itu, Tercatat bahwa bank-bank (pedesaan) Islam pertama di
Indonesia adalah BPR ”Mardatillah” (BPRMD) dan BPR “Berkah Amal
Sejahtera”. Keduanya beroperasi atas dasar hukum Islam (syariah) dan terletak
di Bandung. Keduanya mulai mengoprasikan usahanya pada tanggal 19 Agustus
1991.
Meskipun UU No.7 Tahun 1992 tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan
pendirian bank syariah atau bank bagi hasil dalam pasal pasalnya, kebebasan
yang diberikan oleh pemerintah melalui deregulasi tersebut telah memberikan
pilihan bebas kepada masyarakat untuk merefleksikan pemahaman mereka atas
maksud dan kandungan peraturan tersebut.
2. UU No.10 Tahun 1998
Arah kebijakan regulasi ini dimaksudkan agar ada peningkatan peranan bank
nasional sesuai fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana
masyarakat dengan prioritas koperasi, pengusaha kecil, dan menengah serta
seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Karena itu, UU No.10 Tahun
1998 tentang perubahan atas undang-undang No.7 Tahun 1992 hadir untuk
memberikan kesempatan meningkatkan peranan bank syariah untuk menampung
aspirasi dan kebutuhan masyarakat
Dalam Pasal 6 UU No.10 Tahun 1998 ini mempertegas bahwa:
Pertama, Bank Umum adalah bank yang menyelesaikan kegiatan usaha secara
konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatan usahanya
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Kedua, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan
usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Dalam UU No.10 Tahun 1998 ini pun memberi kesempatan bagi masyarakat
untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan
prinsip Syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada BUK untuk membuka
kantor cabangnya yang khusus menyelenggarakan kegiatan berdasarkan Prinsip
Syariah.
Selain itu, pemerintah juga menjabarkan apakah yang dimaksud dengan Prinsip
Syariah dalam Pasal ini, yaitu terdapat dalam Pasal 1 ayat 13 UU No.10 Tahun
77
Universitas Indonesia
1998: Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara
bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan
usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain
pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan
berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang
dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal
berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya
pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh
pihak lain (ijarah wa iqtina).
3. UU No.23 Tahun 2003
UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah menugaskan kepada BI
untuk mempersiapkan perangkat aturan dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya
yang mendukung kelancaran operasional bank berbasis Syariah serta
penerapan dual bank system.
4. UU No.21 Tahun 2008.
Beberapa aspek penting dalam UU No.21 Tahun 2008:
Pertama, adanya kewajiban mencantumkan kata “syariah” bagi bank syariah,
kecuali bagi bank-bank syariah yang telah beroperasi sebelum berlakunya UU
No.21 Tahun 2008 (Pasal 5 no.4).Bagi bank umum konvensional (BUK) yang
memiliki unit usaha syariah (UUS) diwajibkan mencantumkan nama syariah
setelah nama bank(Pasal 5 no.5).
Konsekuensinya, penamaan suatu UUS pada suatu kantor cabang BUK yang
saat ini kebanyakan disingkat, misalnya Bank X Syariah Cabang Kemayoran,
maka harus di ubah menjadi Bank X Unit Usaha Syariah Cabang Kemayoran.
Kedua, adanya sanksi bagi pemegang saham pengendali yang tidak lulus fit
and proper test dari BI (Pasal 27).
Ketiga, satu-satunya pemegang fatwa syariah adalah MUI. Karena fatwa MUI
harus diterjemahkan menjadi produk perundang-undangan (dalam hal ini
Peraturan Bank Indonesia/PBI), dalam rangka penyusunan PBI, BI membentuk
komite perbankan syariah yang beranggotakan unsur-unsur dari BI,
Departemen agama, dan unsur masyarakat dengan komposisi yang berimbang
dan memiliki keahlian di bidang syariah (Pasal 26).
78
Universitas Indonesia
Keempat, adanya definisi baru mengenai transaksi murabahah. Dalam definisi
lama disebutkan bahwa murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok
barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Menurut UU
No.21 Tahun 2008 disebutkan akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu
barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli
membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
Diubahnya kata “jual beli” dengan kata “pembiayaan”, secara implisit UU
No.21 Tahun 2008 ini ingin mengatakan bahwa transaksi murabahah tidak
termasuk transaksi yang dikenakan pajak sebagaimana yang kini menjadi
masalah bagi bank syariah.
5. Beberapa Peraturan Bank Indonesia mengenai Perbankan syariah
a. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan
penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.
b. PBI No.7/35/PBI/2005 tentang perubahan atas peraturan bank Indonesia
No. 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha
berdasarkan prinsip syariah.
c. PBI No.6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksnakan kegiatan
usaha berdasarkan prinsip syariah
Didalam Pasal 1 angka 3 dan 4 UU NO.10 tahun 1998, bahwa bank
syari‟ah adalah bank umum maupun bank perkreditan rakyat didalam
melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari‟ah atau sesuai
aturan dalam hukum Islam yang berdasarkan pada al-Qur‟an, Hadits, Ijma‟
para sahabat dan Qiyas Ulama. Kemudian dalam Pasal 1 angka 13 UU
No.10 tahun 1998 juga dijelaskan pengertian tentang prinsip syari‟ah:
Prinsip syari‟ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam
antara Bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau
pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai
dengan syari‟ah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil
(mudharabah), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (musyarakah),
prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah) atau
pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan
79
Universitas Indonesia
(ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang
yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)28
3.2.3 Peraturan-Peratran Terkait Hukum Positif Bank Umum Syari’ah
Sejak tahun 1992 dengan diundangkannya Undang-undang No.7 tahun 1992
tentang perbankan menjadi tonggak lahirnya bank berdasarkan syari‟ah
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 huruf (m)UU No.7 Tahun 1992 Juncto
Pasal 13 huruf (c)UU No.10 tahun 1998 dengan tegas membuka kemungkinan
bagi bank untuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip bagi hasil dengan
nasabahnya baik untuk bank umum maupun BPR (Bank Perkreditan Rakyat).
Kegiatan bagi hasil tersebut kemudian oleh UU No. 10 tahun 1998 tentang
perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan, diperluas menjadi kegiatan
apapun dari bank berdasarkan prinsip syari‟ah yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia. Kemudian dalam UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang
telah dirubah dengan UU No.3 tahun 2004, telah memberikan landasan hukum
kepada bank Indonesia untuk menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip
syari‟ah, melakukan pengaturan secara pengawasan terhadap perbankan
berdasarkan prinsip syari‟ah.
Peraturan pemerintah No. 70 tahun 1992 tentang Bank Umum
sebagaimana tertuang didalam Pasal 5 ayat (3) bahwa Bank Umum yang
beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil , dalam rancangan anggaran dan rencana
kerja harus secara tegas mencantumkan kegiatan usaha bank yang semata-mata
berdasarkan prinsip bagi hasil. Kemudian didalam peraturan pemerintah No.72
tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil yang diubah dengan
peraturan pemerintah No. 30 tahun 1999, didalam Pasal 6 ayat (1) bahwa: Bank
Umum atau BPR yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi
hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan
prinsip bagi hasil.
3.3 Pengertian Bank Syari’ah:
28
Pasal 1 ayat 13 UU No.10 tahun 1998
80
Universitas Indonesia
Kata “Bank” berasal dari kata banque dari bahasa perancis, dan dari kata
banco atau banca dalam bahasa Italia, yang artinya adalah bangku atau tempat
duduk. Bank disebut demikian karena pada abad pertengahan orang-orang yang
memberikan pinjaman melakukan usahanya diatas bangku-bangku.29
Menurut OP Simorangkir pengertian bank adalah sebagai berikut:30
“ salah
satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-
jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dana-
dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga atau dengan jalan memperedarkan alat-
alat pembayaran baru berupa uang giral”
Sedangkan Sentosa Sembiring dalam bukunya yang berjudul “ Hukum
Perbankan” memberikan definisi Bank sebagai berikut:31
“ Bank adalah suatau
badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak dibidang jasa keuangan, Bank
sebagai badan hukum berarti secara yuridis merupakan subjek hukum yang dapat
mengikatkan diri kepada pihak ketiga. Dengan demikian hukum perbankan dapat
dirumuskan sebagai berikut: serangmkaian kaidah-kaidah yang mengagthur
tentang badan usaha perbankan. Kaidah-kaidah yang dimaksud disini adalah baik
yang terdapat dalam hukum positif maupun dalam praktek perbankan.
Menurut A. Abdurrahman, Bank adalah suatu jenis pranata finansial yang
melaksanakan jasa-jasa keuangan yang beraneka ragam, seperti memberi
pinjaman, mengedarkan mata uang, bertindak sebagai penyimpan benda-benda
berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan. Sedangkan menurut Henry
Campbell dalam Black law Dictionary (1968). Bank adalah suatu institusi yang
mempunyai peran besar dalam dunia komersial, yang mempnyai wewenang untuk
menerima deposito, memberikan pinjaman dan memberikan promissory notes
yang sering disebut dengan Bank belles atau Bank Notes. Namun demikian fungsi
29
Lembaga Kajian Hukum Ekonomi, Sejarah Perkembangan Metode Perbankan di
Indonesia (jakarta 1990) hlm.1
30 OP Simorangkir, dalam Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, Mandar Madju,
Bandung, 2000 hal 1
31 Ibid.
81
Universitas Indonesia
bank yang orisinil hanya menerima deposito berupa uang logam, plate, mas dan
lain-lain.32
Menurut Kamus Istilah Hukum Pockema Andrea yang dimaksud dengan
bank adalah lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam
menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubung dengan
adanya cek, dan hanya dapat diberikan kepada Bankir, maka bank dalam arti luas
adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaanya secara teratur menyediakan
uang untuk pihak ketiga.33
Sedangkan Definisi Bank dan perbankan sesuai dengan Pasal 1 Undang-
Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun
1992, disebutkan bahwa pengertian bank adalah sebagai berikut: “ Bank adalah
badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup
rakyat banyak”. Sedangkan perbankan didefinisikan sebagai berikut: “segala
sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha
serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.
Sedangkan “Bank Syari‟ah” adalah istilah yang di pakai di Indonesia
untuk menyatakan suatu jenis bank yang dalam pelaksanaanya berdasarkan
prinsip syari‟ah. Dan “Bank Islam” (Islamic Bank) adalah istilah yang digunakan
secara luas dinegara lain untuk menyebut bank dengan prinsip syari‟ah, walaupun
masih banyak istilah lain yang digunakan untuk menyebut Bank Islam tersebut,
seperti Interest free bank, lariba bank, shari’a bank dan lain-lain.
Secara resmi sebagaimana tersebut dalam peraturan perundang-undangan
Rebublik Indonesia, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat
dalam bentuk kredit dan /atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan
taraf hidup rakyat.34
32
Hukum Perbankan Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung 1999 hlm 13 – 14.
33 Zainal Asikin, Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 1995, hlm. 4.
34 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari‟ah.
82
Universitas Indonesia
Istilah Syari’ah berasal dari bahasa arab yang berarti “ jalan menuju
sumber kehidupan” , yang secara hukum Islam diartikan sebagai hukum atau
peratutan yang ditentukan oleh Allah SWT untuk hamba-Nya sebagaimana yang
terkandung didalam Al-Qur‟an dan dalam al-Hadits.35
Sebagian ulama
berpendapat dengan redaksi yang berbeda bahwa secara harfiah syari‟ah berarti
jalan yang ditempuh atau garis yang semestinya dilalui. Secara terminologi
menurut Adiwarman Karim Syariah adalah peraturan-peraturan dan hukum yang
telah digariskan oleh Allah, atau telah digariskan pokok-pokoknya dan
dibebankan kepada kaum muslimin supaya mematuhinya, agar jalan itu diambil
oleh umat Islam sebagai penghubung diantaranya dengan sesama manusia.36
Istilah Bank Syari‟ah itu sendiri berasal dari dua kata yaitu Bank dan
Syari‟ah, yang didalam istilah internasional dikenal dengan istilah Islamic
Banking atau disebut juga Interest-free Banking.37
Secara etimologis, kata
“banco” dalam bahasa Italia berarti peti, lemari atau bangku. Kata peti atau lemari
mengandung pengertian fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga,
seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya. Dalam Al-Qur‟ah istilah
bank tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi jika yang dimaksud dengan bank
adalah sesuatu yang memiliki unsur seperti struktur, mamajemen, fungsi hak dan
kewajiban maka semua itu disebutkan dengan jelas seperti : zakat, shadaqah,
ghonimah (rampasan perang) dan yang memiliki fungsi yang dilaksanakan oleh
peran tertentu dalam kegiatan ekonomi.38
Menurut M. Amin Aziz, Bank adalah lembaga yang mendapatkan izin
untuk mengarahkan dana masyarakat berupa simpanan dan menyalurkan pada
masyarakat berupa pinjaman, sehingga berfungsi sebagai sarana perantara bagi
penabung yang mengalami surplus dana dengan pinjaman yang mengalami defisit
35
Wirdyanigsih, dkk, Bank dalam Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta, Kencana Prenada
Media, 2007) hlm.4
36 Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan. (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2004) hlm. 7
37 Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah, edisi revisi, unit penerbit dan percetakan (UPP)
AMPYKPN, Yogyakarta 2005 hal 13.
38 Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syari’ah, Alfabeth (jakarta 2002) hlm 2-3
83
Universitas Indonesia
dana dalam membiayai usaha yang dilakukan.39
Menurut Muhammad dalam
bukunya Lembaga Keuangan Umat Kontemporer bahwa bank adalah lembaga
perantara keuangan atau bisa disebut financial intermediary. Artinya, lembaga
bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang.
Oleh karena itu usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang
merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama.40
Menurut Syafi‟i Antonio dan Karnaen Perwataatmaja bank Islam adalah
bank yang beroprasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari‟ah Islam, yakni bank
yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syari‟ah islam
khususnya yang menyangkut tatacara bermu‟amalah secara Islam. Dalam tatacara
bermu‟amalah itu dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-
unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan
pembiayaan perdagangan.41
Beliau mengatakan pula lebih spesifik bahwa bank islam adalah: bank
yang tatacara beroperasinya mengacu pada ketentuan al-Qur‟an dan al-Hasits,
yakni bank yang tatacara beroperasinya itu mengikuti suruhan dan larangan yang
tercantum dalam a-Qur‟an dan al-Hadits. Sesuai dengan suruhan dan larangan itu
maka yang dijauhi adalah praktik-praktik yang mengandung unsur-unsur riba,
sedangkan praktik-praktik yang diikuti adalah usaha-usaha yang dilakukan di
zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi
tidak dilarang oleh beliau.42
Demikian pula Cholil Uman mendefinisikan bank syari‟ah dengan
memperbandingkan antara Bank Islam dengan Bank Non Islam sebagai berikut:
bank islam adalah sebuah lembaga keuangan yang menjalankan operasinya
menurut hukum Islam. Sudah tentu bank islam tidak memakai sistem bunga,
sebab bunga dilarang oleh islam. Sedangkan bank non islam adalah sebuah
39
M. Anin Aziz, Mengembangkan Bank Islam di Indonesia, Bank, Jakarta, 1992. hlm.1
40 Muhammad, Lembaga keuangan Umat Kontemporer, UII Tes, (yogyakarta, 2000) hal.
63
41 Karnaen Perwataatmaja dan Syafi‟i Antonio, 1992, Apa dan Bagaimana Bank Islam,
Yogyakarta: Dana Bahakti Wakaf, hlm 1-2.
42 Ibid
84
Universitas Indonesia
lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana untuk
disalurkan kepada yang memerlukan dana guna investasi dalam usaha-usaha yang
produktif dan lain-lain dengan sistem bunga.43
Dari beberapa pengertian bank islam yang telah dikemukakan oleh para
ahli tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa bank syari‟ah adalah suatu
lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang
berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan
kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu bank syari‟ah dapat juga
disebut sebagai Islamic Banking atau Interest fee banking. Yaitu suatu system
perbankan yang dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan system
bunga (riba), Spekulasi (maisir) dan ketidak pastian atau ketidak jelasan
(gharar).44
Bank Syari‟ah sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai mekanisme
dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal (depositor) dan mempunyai
kewajiban (liability) untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi
asetnya dengan pembiayaan yang sesuai syari‟at Islam. Pada sisi kewajiban,
terdapat dua kategori utama yaitu: Infest-fee Current and Saving accounts yang
berdasarkan pada prinsip PLS (Profit and Loss Sharing)antara pihak bank dengan
pimhak depositor, sedangkan pada sisi asset yang termasuk didalamnya segala
bentuk pola pembiayaan yang bebas riba dan sesuai dengan prinsip syari‟ah.
Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syari‟ah maksudnya adalah
dalam operasinya tersebut mengikuti ketentuan-ketentuan syari‟ah khususnya
yang menyangkut tatacara bermu‟amalah secara Islam. Dalam bermu‟amalah
tersebut menjauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsure-unsur
riba dan menggantinya dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil
dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman
43
Cholil Uman, 1994, Agama Menjawab tentang berbagai masalah abad modern,
Surabaya: Ampel Suci Surabaya, hlm.5-6
44 Ibid., hlm.2
85
Universitas Indonesia
Rasulullah atau bentuk-bentuk lain yang telah ada sebelumnya tetapi tidak
dilarang oleh beliau.45
Bank Islam/ bank syari‟ah adalah sebuah bentuk dari bank modern yang
didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam
yang menggunakan konsep berbagi resiko sebagai metode utama, dan
mentiadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan
sebelumnya.46
Terdapat tujuh prinsip ekonomi Islam yang menjiwai bank Syari‟ah, yaitu:
(1). Keadilan, kesamaan dan solidaritas
(2). Larangan terhadap Objek dan makhluk
(3). Pengakuan kekayaan Intelektual
(4). Harta sebaiknya digunakan dengan rasional dan baik (fair way)
(5). Tidak ada pendapatan tanpa usaha dan kewajiban
(6). Kondisi umum dari kredit (meliputi: peminjam yang mengalami kesulitan
keuangan sebaiknya diperlakukan secara baik, diberi tangguh waktu bahkan
akan lebih baik jika diberi keringanan. Kemudian terdapat beberapa
perbedaan pendapat mengenai hukum selisih dan harga spot, ada yang
berpendapat bahwa itu adalah suku bunga implicit dan juga ada yang
berpendapat bahwa hal tersebut dibolehkan untuk mengkomodasi biaya
transaksi bukan biaya dari pembiayaan).
(7). Dualiti risiko, disatu sisi sebagai bagian dari persetujuan kredit (liability)
usaha produktif yang merupakan legitimasi dari bagi hasil, dilain sisi
sebaiknya risiko diambil secara hati-hati, risiko yang tak terkontrol
sebaiknya dihindari.
Kelahiran bank syari‟ah (Bank Islam) dilandasi bahwa segala sesuatu
aktivitas seorang muslim harus didasarkan kepada syari‟at Islam. Islam tidak
hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (ibadah), tetapi juga mengatur
45
A. Karnaen Perwaatmadja, “Bank, Asuransi dan Hukum Islam”, (Bahan Kuliah Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, semester gasal tahun ajaran 2000/2001), hal.1
46 Abdul Manan, Sistem Ekonomi Berdasarkan Syari’ah (Artikel dalam Suara Udilag,
Vol.3,No.IX, September 2006, Jakarta, MA-RI
86
Universitas Indonesia
hubungan antara manusia dengan manusia (muamalat). Allah memberikan
petunjuk melalui para Rasul-Nya yaitu mengenai segala sesuatu yang dibutuhkan
manusia baik akidah, akhlak, maupun syari‟ah. Dengan demikian hubungan dalam
keseharian termasuk dalam bidang keuangan dan perbankan haruslah dilandasi
dengan prinsip-prinsip yang diperbolehkan oleh syari‟at Islam. Al-Qur‟an
melarang adanya riba, sebagaimana Allah berfirman dalam al-Qur‟an surat Ali
Imron ayat 130:
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba
dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu
mendapat keberuntungan.47
Didalam Ushul Fiqh terdapat kaidah:
ما ال يتم الىاجب االبه فهى
واجبyakni sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan suatu kewajiban,
maka wajib diadakan. Mencari nafkah itu bagian dari kegiatan perekonomian dan
pada saat ini perekoomian itu tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga
perbankan, sehingga lembaga perbankan itu wajib diadakan agar perekonomian
berjalan sempurna.48
Perbankan syari‟ah merupakan suatu system perbankan yang
dikembangkan berdasarkan hukum Islam. Dimana usaha ini didasari oleh larangan
untuk memungut ataupun memberikan pinjaman dengan perhitungan bunga
(riba) dan larangan berinvestasi didalam usaha-usaha yang berkaitan dengan
barang-barang yang tidak Islami (haram). Dalam Pedoman Akuntansi Perbankan
Syari‟ah Indonesia (PAPSI), Bank Indonesia mendefinisikan Perbankan Syari‟ah
47
Departemen Agama Rebublik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, Jakarta. 2008
48 Lihat A. Adiwarman Karim, Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan, edisi ke -3
Jakarta: 2008, hlm.14 -15.
87
Universitas Indonesia
sebagai berikut:49
“ Bank Syari‟ah adalah bank yang berdasarkan antara lain asas
kemitraan, keadilan, transportasi dan universal serta melakukan kegiatan usaha
perbankan berdasarkan prinsip syari‟ah.
Falsafah besar beroperasinya bank syari‟ah yang yang menjiwai seluruh
hubungan transaksinya adalah efisiensi, keadilan dan kebersamaan. Efisiensi
mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh
keuntungan sebesar-besarnya. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak
dicurangi, ikhlas dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan
keluarannya. Sedangkan kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan
bantuan dan nasehat untuk saling meningkatkan produktivitas.50
3.4 Akad-Akad Yang Dipergunakan Dalam Perbankan Syari’ah
Dalam perbankan syari‟ah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi
duniawi dan ukhrawi karena akad dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali
nasabah berani melanggar kesepakatan perjanjian yang telah dilakukan bila
hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tetapi tidak demikian bila
perjanjiian tersebut memiliki pertanggungjawabn hingga yaumil qiyamah.51
Secara garis besar hubungan ekonomi berdasarkan Syariah Islam
ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari lima (5) dasar akad. Bersumber
dari kelima konsep dasar ini maka dapat ditemukan produk-produk lembaga
keuangan Bank Syariah dan lembaga keuangan bukan Bank Syariah untuk
dioperasikan. Lima akad tersebut tersebut adalah:
1. Akad Mudharabah
Merupakan Perjanjian antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai
pemilik dana (sahibul maal) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (mudharib)
untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil
atas keuntungan yang akan diperoleh, sedangkan kerugian yang timbul adalah
49
Bank Indonesia, Pedoman Akuntansi Perbankan Syari’ah Indonesia(PAPSI),
Jakarta:2003.
50 Azia Amin, Mengembangkan Bank Islam di Indonesia, Buku 2 (Jakarta: Bangkit, 2003)
hlm. 16
51 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani
Pers, Cet.1 hlm.29
88
Universitas Indonesia
risiko pemilik dana kecuali mudharib melakukan kesalahan yang disengaja, lalai
atau menyalahi perjanjian.
Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudharib, murabahah
dibedakan atas:
a. Mudharabah mutlaqah,
Dimana pengelola yaitu mudharib diberi kesempatan untuk mengelola
modal dengan usaha apasaja yang dapat mendatangkan keuntungan dan
tidak dibatasi pada daerah tertentu namun bidang usaha yang dikelola tetap
tidak boleh bertentangan dengan hokum syari‟ah.
b. Mudharabah muqayyaddah,
Dimana mudharib harus mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan oleh
shahibul maal seperti berdagang barang tertentu, di daerah tertentu dan
membeli barang pada orang tertentu. Syarat-syarat yang ditentukan oleh
shahibl maal juga tidak boleh bertentangan dengan syari‟ah.52
2. Akad Musyarakah
Merupakan ikatan kerjasana antara orang-orang yang berserikat dalam hal
modal dan keuntungan.53
Syirkah secara umum terbagi dalam tiga bentuk, yaitu syirkah ibahah, syirkah
amlak, dan syirkah uqud54
.
1) Syirkah ibahah yaitu: persekutuan hak semua orang untuk dibolehkan
menikmati manfaat sesuatu yang belum ada dibawah kekuasaan
seseorang.
2) Syirkah amlak (milik), yaitu: persekutuan antara dua orang atau lebih
untuk memiliki suatu benda.
3) Syirkah Akad, yaitu: persekutuan antara dua orang atau leih yang timbul
dengan adanya perjanjian.
52
Gemala Dewi dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana. 2005., 135-
136.
53 Ibid., hlm. 127.
54 Wirdyaningsih, Perjanjian Kerjasama Modal Dan Jasa (Al-Mudharabah) Menurut
Hukum Islam Pada Koperasi Ridho Gusti Skripsi Sarjana FHUI tahun 1992.
89
Universitas Indonesia
3. Akad Wadi’ah (Simpanan Murni)
Al-Wadi’ah merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Syariah untuk
memberikan kesempatan kepada pihak yang mempunyai dana lebih untuk
menyimpan dananya dalam bentuk al-wadi’ah. Fasillitas ini biasanya diberikan
untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan
deposito. Dalam dunia perbankan konvensional konsep al-wadi’ah identik dengan
Giro.55
Adapun beberapa istiah yaitu:56
a. Penerima simpanan disebut yad al-amanah yang artinya tangan amanah. Si
penyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan
yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau
kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan.
b. Penggunaan uang titipan harus terlebih dulu meminta izin kepada si pemilik
uang dan dengan catatan si pengguna uang menjamin akan mengembalikan
uang tersebut secara utuh. Dengan demikian prinsip yad al-amanah (tangan
amanah) menjadi yad adh-dhamanah (tangan penanggung).
c. Konsekuensi dari diterapkannya prinsip yad adh-dhamanah pihak bank akan
menerima seluruh keuntungan dari penggunaan uang, namun sebaliknya bila
mengalami kerugian, pihak bank harus menanggung sendiri kerugian tersebut.
d. Sebagai imbalan kepada pemilik dana disamping jaminan keamanan uangnya
juga akan memperoleh fasilitas lainnya seperti insentif atau bonus untuk giro
wadiah. Artinya bank tidak dilarang untuk memberikan jasa atas pemakaian
uangnya berupa insentif atau bonus, dengan catatan tanpa perjanjian terlebih
dulu baik nominal maupun persentase dan ini murni merupakan kebijakan
bank sebagai pengguna uang. Pemberian jasa berupa insentif atau bonus
biasanya digunakan istilah nisbah atau bagi hasil antara bank dengan nasabah.
55
http://indridwipertiwi.blogspot.com/2014/03/manajemen-perbankan-syariah.html, Indri
Dwi Pertiwi: “Manajemen Perbankan Syari‟ah”. Diakses tanggal 07 juli 2014.
56 http://killer-killermaniac2.blogspot.com/2012/04/simpanan-giro-wadiah.html, Simpanan
Giro Wadi‟ah, diakses tanggal 07 juli 2014.
90
Universitas Indonesia
Bonus biasanya diberikan kepada nasabah yang memiliki dana rata-rata
minimal yang telah ditetapkan.
e. Dalam praktiknya nisbah antara bank (shahibul maal) dengan
deposan (mudharib) biasanya bonus untuk giro wadiah sebesar 30%, nisbah
40%:60% untuk simpanan tabungan dan nisbah 45%:55% untuk simpanan
deposito.
4. Akad At-Tijarah (Jual Beli)
At-Tijarah merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli dimana
bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat
nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank,
kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah
beli ditambah keuntungan (margin).57
Prinsip At-Tijarah terdiri dari:58
a. Bai‟al Murabahah
Akad jual beli antara dua belah pihak dimana pembeli dan penjual
menyepakati harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah ongkos
pembelian dan keuntungan bagi penjual. Nasabah membayar harga barang
pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.59
b. Bai‟ as-Salam
Pembelian barang dengan pembayaran dimuka dan barang diserahkan
kemudian.
c. Bai‟ al-Ishtisna
Merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam
kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat
barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli
57
http://najae9.blogspot.com/2014/02/bank-konvensional-dan-bank-syariah.html, Bank
Konvensional dan Bank Syari‟ah, diakses 7 juli 2014.
58 Ibid
59 Ibid
91
Universitas Indonesia
barang menurut spesifikasi yang telah disepaati dan menjualnya kepada
pembeli akhir.60
3.5 Rukun dan Syarat Dalam Perbankan Syari’ah
Ketentuan rukun dan akad transaksi dalam perbankan syari‟ah berbeda
dengan bank konvensional. Rukun dan akad dalam perbankan syari‟ah adalah:61
1. Penjual
2. Pembeli
3. Barang
4. Harga
5. Akad/ijab dan qabul
Syarat pelaksanaan transaksi dalam perbankan syari‟ah yaitu:
1. Barang dan jasa harus halal menurut syari‟at, sehingga transaksi atas barang
dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syari‟ah.
2. Harga barang dan jasa harus jelas (telah ditetapkan)
3. Tempat penyerahan (delivery) harus jelas, karena berdampak pada biaya
transportasi.
4. Barang objek transaksi harus sepenuhnya berada dalam objek kepemilikan,
artinya tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti
yang terjadi pada transaksi short sale yang terjadi dalam pasar modal.62
3.6 Prinsip Hukum Perbankan Syari’ah
Prinsip dasar perbankan syari‟ah adalah aturan perjanjian berdasarkan
hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana pembiayaan
kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syari‟ah. Beberapa
prinsip hukum yang di anut oleh perbankan syari‟ah antara lain:
60
Ibid
61 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani
Pers, Cet.1 hlm.31
62 Ibid
92
Universitas Indonesia
1. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman
dengan nilai yang ditentukan sebelumnya maka dilarang.
2. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil
usaha institusi yang meminjam dana.
3. Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang dari uang”
4. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak
memiliki nilai instrinsik.
5. Unsur gharar (ketidak pastian, spekulasi) tidak diperkenankan
6. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka
peroleh dari sebuah transaksi.
7. Investasi hanya dapat diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan
dalam Islam
8. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syari‟ah63
3.7 Tujuan Perbankan syariah:
Perbankan syariah memiliki tujuan yang sama seperti perbankan
konvensional, yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan
dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha,
atau kegiatan lainnya yang sesuai. Prinsip hukum Islam melarang unsur-unsur di
bawah ini dalam transaksi-transaksi perbankan tersebut:64
1. Perniagaan atas barang-barang yang haram.
2. Bunga (ربا riba).
3. Perjudian dan spekulasi yang disengaja (ميسر maisir) serta
4. Ketidakjelasan dan manipulatif (غرر gharar).
Bank syari‟ah didasarkan pada al-Qur‟an dan al-Hadist sebagai pedoman
hidup umat Islam. Filosofi dan dasar perbankan syari‟ah meliputi 3 aspek, yaitu
produktif, adil dan memiliki akhlaq atau moralitas usaha. Produktif berarti harta
yang dipergunakan untuk kemaslahatan dan kesejahtraan. Oleh karenanya harta
juga tidak boleh menganggur dan diperkenankan memperoleh laba. Sedangkan
adil berarti dilarangnya riba dan diharuskan dilakukan pembagian hasil risiko.
63
Shariahbank.blogspot.com/2008_07_01_archive.htmw(UUBS), 13 Juli 2011.
64 Muhammad, Syafi'i Antonio, Bank Syariah, Dari Teori ke Praktik, penyunting Dadi
M.H. Basri, Farida R. Dewi, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press. ISBN 979-561-688-9, 2001.
93
Universitas Indonesia
Akhlak dan moralitas usaha meliputi larangan investasi pada usaha maksiat dan
merusak lingkungan serta larangan bersepekulasi.65
Larangan riba yang terdapat dalam al-Qur‟an tidak diturunkan sekaligus,
melainkan diturunkan dalam beberapa tahap, anta lain:
a. Tahap pertama terdapat dalam surat ar-Ruum ayat 39
Artinya: Dan apa yang kamu berikan sebagai tambahan (riba) untuk menambah
harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan zakat yang
kamu berikan karena megharap ridha Allah, maka mereka (yang memberikan
zakat itu) melipat gandakan pahalanya.66
b. Tahap ke dua terdapat dalam Surat an-Nisa ayat 161:
Artinya: Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya
mereka telah dilarang melakukannya, dan karena mereka memakan harta
benda orang lain dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk
orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.
c. Tahap yang ke tiga terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 275:67
65
Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Perbankan, Peluang Bank Syari’ah. Media
Indonesia” 28 Mei 2001
66 Departemen Agama Rebublik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, Jakarta. 2008, al-
Qur‟ah surat ar-Ruum ayat 39.
67 Departemen Agama Rebublik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, Jakarta. 2008
94
Universitas Indonesia
Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan)
penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka
berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal
Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang
telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari
mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum
datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali
(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka
kekal di dalamnya.68
Berdirinya bank syari‟ah memiliki tujuan sebagai berikut:69
1. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan
kualitas kehidupan sosial masyarakat banyak.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan
terutama dibidang ekonomi keuangan.
3. Berkembangnya lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat
berdasarkan efisiensi dan keadilan akan mampu meningkatkan partisipasi
masyarakat sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi masyarakat
banyak dengan antara lain memperluas jaringan lembaga-lembaga
keuangan perbankan ke daerah-daerah terpencil.
4. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomis
berprilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.
5. Berusaha membuktikan bahwa konsep perbankan Islam menurut syari‟ah
Islam dapat beroperasi, tumbuh dan berkembang melebihi bank-bank
dengan sistem lain.
68
Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang
disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan
barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan
demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang
dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat
Arab zaman jahiliyah.
69 M. Amin Aziz, Mengembangkan Bank Islam di Indonesia, Bangkit, Jakarta: 1996, hlm.
9-11
95
Universitas Indonesia
Tujuan ditetapkannya syari‟at tidak lain adalah untuk kemaslahatan manusia.
Hal ini dapat dilakukan dengan menghilangkan riba dalam aktivitas ekonomi.
Tujuan didirikannya bank syari‟ah itu sendiri mengarahkan kegiatan ekonomi
umat untuk bermu‟amalah secara Islam, khususnya mu‟amalah yang berhubungan
dengan perbankan agar terhindar dari praktek-praktek riba ajau jenis-jenis
usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur penipuan.
Bank syari‟ah ini didirikan dengan memiliki beberaa tujuan diantaranya adalah
pertama untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi, dengan jalan
meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi sehingga tidak terjadi
kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang
membutuhkan dana. Kemudian yang kedua untuk meningkatkan kualitas hidup
umat dengan jalan membuka peluang beruaha yang lebar untuk menjaga stabilitas
ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas-aktivitas bank Islam diharapkan mampu
menghindari inflasi dan negative spread akibat penerapan suku bunga. Dan yang
ke-tiga menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan,
khususnya bank serta menanggulangi kemandirian lembaga keuangan dari
pengaruh gejolak moneter baik dalam maupun luar negeri.
Abdul Gani Abdullah mengemukakan dalam analisis dan evaluasi hukum yang
dilakukannya terhadap perbankan syari‟ah, menemukan setidaknya empat hal
yang menjadi tujuan pembangunan berdasarkan prinsip syari‟ah yaitu:70
a. Untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak
dapat menerima konsep bunga
b. Terciptanya dual banking sistem di Indonesia yang mengakomodasi
terlaksananya sistem perbankan konvensional dan perbankan syari‟ah
dengan baik dalam proses kompetisi yang sehat, dimana didukung oleh
pola prilaku bisnis yang bernilai dan bermoral.
c. Mengurangi risiko kegagalan sistem keuangan Indonesia.
d. Mendorong peran perbankan dalam menggerakkan sektor riil dan
membatasi segala bentuk eksploitasi yang tidak produktif, serta
mengabaikan nilai-nilai moral.
70
Arifin Hamid, Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syari’ah) di Indonesia Aplikasi dan
Prospektifnya, (Bogor: Ghalia Indonesia,2007) hal.129
96
Universitas Indonesia
Fungsi dan peran perbankan syari‟ah diantaranya tercantum dalam pembukaan
standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing
Organization for Islamic Financial Institution), sebagai berikut:
1. Manajeer investasi, bank syari‟ah dapat mengelola dana nasabah
2. Investor, Bank Syari‟ah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya
maupun dana nasabah yang dipercayakan padanya
3. Penyediaan jasa keuangan dan lalulintas pembayarann.
4. Pelaksanaan kegiatan sosial, contoh: kewajiban mengeluarkan dana dan
mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat
serta dana sosial lainnya.71
Bank syari‟ah memiliki fungsi yang berbeda dengan bank konvensional
Bank Islam diperkenankan untuk mengeluarkan produk, jasa dan kegiatan usaha
perbankan yang baru, dimana sebelumnya tidak ada dan belum dikenal pada
zaman Rasulullah asal hal itu tidak bertentangan dengan al-Qur‟an maupun al-
Hadits. Pada bank Islam umumnya dibentuk suatu lembaga pengawas yang
bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan atas produk, jasa dan
kegiatan usaha bank islam tersebut agar tidak berlawanan dengan ketentuan serta
prinsip-prinsip syari‟ah sebagaimana dalam al-Qur‟an dan al-Hadits. Lembaga
pengawas inilah yang akan memberikan fatwa kepada bank yang bersangkutan.
Sepanjang bank konvensional tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip
islam maka bank-bank Islam telah mengadopsi sistem dan prosedur perbankan
yang ada, namun bila bertentangan dengan prinsip syari‟ah maka bank islam harus
merencanakan dan menerapkan sistem sendiri guna menyesuaikan aktivitas
perbankan mereka dengan prinsip-prinsip syari‟at Islam. Untuk itu maka
pengawas perbankan syari‟ah yang lebih kita kenal dengan istilah DPS (Dewan
pengawas Syari‟ah) berfungsi memberikan masukan kepada bank Syar‟ah guna
memastikan bank islam tidak terlibat dengan unsur-unsur yang tidak disetujui oleh
Islam.72
71
M. Sholahuddin, Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam, Surakarta: UMS Pers. 2006,
hlm. 19
72 Wirdyaningsih, et,al.,2005, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana
Prenada dan Badan Penerbit Fakultas hukum Universitas indonesia, hlm 39.
97
Universitas Indonesia
Adapun tujuan didirikannya bank syari‟ah adalah sebagai berikut:
1. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan
kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dengan adanya lembaga keuangan
diharapkan akan tersedianya kesempatan yang lebih baik untuk
mengumpulkan modal dan pemanfaatan dana sehingga akan mengurangi
kesenjangan sosial ekonomi dan dengan demikian akan memberikan
sumbangan peninigkatan pembangunan nasional yang semakin mantap,
antara lain dengan cara meningkatkan kualitas usaha dan kegiatan usaha.73
a. Sistem bagi hasil yang berdasarkan atas keadilan dan peningkatan
euntungan bagi kedua belah pihak akan merangsang orang-orang dan
pengusaha-pengusaha kecil yang lemah permodalannya untuk bekerja
sama dengan bank islam dalam permodalannya guna mendirikan usaha
baru dan mengembangkan usaha yang tengah dijalankan. Hal seperti ini
diharapkan akan mengakibatkan munculnya kegiatan-kegiatan usaha
baru didalam masyarakat sehingga kuantitas usaha dan kualitas usaha
akan mengalami peningkatan.
b. Dengan munculnya kegiatan-kegiatan usaha baru dan pengembangan
usaaha yang telah ada maka akan terbuka luas lapangan kerja baru yang
akan mengurangi angka pengangguran dan akan meningkatkan
pendapatan masyarakat.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan,
terutama dalam bidang ekonomi karena:
a. Masih banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank, hal ini
terjadi karena masih banyak masyarakat islam beranggapan bunga bank itu
riba dan diharamkan dalam islam selain itu banyak masyarakat kecil yang
masih belum terbiasa pinjam ataupun menabung di bank.
b. Dengan adanya bank syari‟ah masyarakat Islam yang semula enggan
berhubungan dengan bank akan terasa terpanggil berhubungan dengan bank
Syari‟ah, ini merupakan sumbangan bagi pembangunan nasional.
73
Rachmadu Usman, Aspek hukum perbankan syari’ah,Jakarta: Sinar Grafika, cet. I, 2012,
hlm.37
98
Universitas Indonesia
3. Berkembangnya lembaga bank dan sistim perbankan yang sehat berdasar
efisiensi dan keadilan yang akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat
kemudian menggalakkan usaha-usaha ekonomi masyarakat banyak sehingga
memperluas jaringan lembaga-lembaga keuangan perbankan ke daerah-daerah
terpencil.
4. Ikhtiar ini akan sekaligus mendidik dan membimbing masyarakat untuk
berpikir secara ekonomis, berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas
hidup mereka.
5. Berusaha membuktikan bahwa konsep perbankan menurut syari‟ah dapat
beroperasi, tumbuh dan berkembang melebihi bank-bank dengan sistem lain.74
3.8 Ciri-Ciri Bank Syari’ah dan Perbedaanya dengan Bank Konvensional
3.8.1 Ciri-ciri bank syari’ah
a. Keuntungan dan beban biaya yang disepakati tidak kaku dan ditentukan
berdasarkan kelayakan tanggungan risiko dan pengorbanan masing-masing
b. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu kontrak. Sisa
utang selepas kontrak dilakukan kontrak baru
c. Penggunaan persentase untuk perhitungan keuntungan dan biaya
administrasi selalu dihindarkan.
d. Pada bank Islam (bank syari‟ah) tidak mengenal keuntungan pasti (fixed
return), ditentukan kepastian setelah mendapat keuntungan, bukan
sebelumnya.
e. Uang dari jenis yang sama tidak dapat diperjualbelikan atau disewakan
atau di anggap barang-barang dagangan, oleh karena itu seharusnya bank
syari‟ah tidak memberikan pinjaman berupa uang tunai tetapi berupa
pembiayaan atau talangan dana untuk pengadaan barang dan jasa.75
74
M.Amin Aziz (2), Op.Cit., hlm 10-11.
75 M. Amin Aziz (1) Op.Cit., hlm.5-6
99
Universitas Indonesia
8.2. Perbandingan Antara Bank Syariah Dan Bank Konvensional Adalah
Sebagai Berikut76
No Karakter Bank Islam Bank Konvensional
1 Eksistensi Dan
Legalitas
Hukum Islam dan Hukum
Positif
Hukum Positif
2 Dasar Hukum Produk
Dan Akad
Hukum Islam Dan Hukum
Positif
Hukum Positif
3 Fungsi Ekonomi dan Sosial
(keagamaan)
Ekonomi
4 Orientasi Usaha Profit dan falah oriented Profit Oriented
5 Prinsip Operasional Berdasarkan asas prinsip
syari‟ah (bagi hasil, jual
beli, sewamenyewa, pinjam
meminjam)
Berdasarkan Asas Prinsip
Konvensional berdasarkan
bunga
6 Investasi Halal Halal dan Haram
7 Hubngan Bank dengan
Nasabah
Kemitraan Dan Sejajar Debitur dan Kreditur
8 Penentuan
Keuntungan atau
Imbalan
Kesepakatan Bersama Sepihak Oleh Bank
9 Penggunaan Dana Riil (User Of Real Funds) Creator of Money Supply
10 Penghimpunan dan
penyaluran dana
sesuai fatwa Dewan
Pengawas Syariah
tidak diatur oleh dewan
Pengawas
11 Pengawasan Bank Indonesia, Dewan Bank Indonesa
76
Rahmadi Usman, Aspek hokum Perbankan Syari’ah di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika,
2012., hlm. 41.
100
Universitas Indonesia
Syari‟ah Nasional dan
dewan pengawas Syari‟ah
3.9 Sistem Operasional Bank Syariah.
Prinsip utama operasional bank berdasarkan Prinsip Syariah adalah hukum
Islam yang bersumber dari Al Qur‟an dan Al Hadist. Kegiatn operasional bank
harus memperhatikan perintah dan larangan kedua sumber tersebut. Larangan
terutama berkaitan dengan kegiatan bank yang dapat diklasifikasikan sebagai riba.
Perbedaan utama antara kegiatan bank berdasarkan prinsip syariah dengan bank
konvensional pada dasarnya terletak pada sistem pemberian imbalan atau jasa atas
dana.
Dalam menjalankan operasionalnya, bank berdasarkan Prinsip Syariah
tidak menggunakan sistem bunga dalam menentukan sitem imbalan atas dana
yang digunakan atau ditipkan oleh suatu pihak. Penentuan imbalan terhadap dana
yang dipinjamkan maupun dana yang disimpan di bank didasarkan pada prinsip
bagi hasil sesuai dengan hukum Islam. Perlu diakui bahwa dalam hukum Islam,
bunga bank adalah riba dan diharamkan. Ditinjau dari sisi pelayanan terhadap
masyarakat dan pemasaran, adanya bank atas dasar prinsip Syariah merupakan
usaha untuk melayani dan mendayagunakan segmen pasar perbankan yang tidak
setuju atau tidak menyukai sistem bunga.
3.10 Sumber-Sumber Dana Bank Syariah
Perbankan syari‟ah merupakan lembaga yang menghimpun, mengelola
dan menyalurkan dana. Oleh sebab itu, bank syari‟ah membutuhkan sumber-
sumber dana yang akan dikelola.
Metode penghimpunan dana yang ada pada bank konvensional didasari
teori yang diungkapkan Keynes yang mengemukakan bahwa orang membutuhkan
uang untuk tiga Kegunaan, yaitu fungsi transaksi, cadangan, dan investasi. Oleh
karena itu, produk penghimpunan dana pun disesuaikan dengan tiga fungsi
tersebut, yaitu berupa giro, tabungan, dan deposito.
101
Universitas Indonesia
Berbeda dengan hal berikut, bank syariah tidak melakukan pendekatan
tunggal dalam menyediakan produk penghimpunan dana bagi nasabahnya. Pada
dasarnya, dilihat dari sumbernya, dana bank syariah terdiri atas:
3.10.1 Sumber Dana
Sebagai salah satu lembaga yang berfungsi untuk menghimpun dana
masyarakat, bank syariah harus memiliki sumber dana optimal sebelum disalurkan
kembali ke masyarakat. Disamping itu, sebagai bank syariah yang di tuntut untuk
mempraktikan kaidah Islam, maka perlu dipahami terlebih dahulu dana
masyarakat dan transaksi-transaksinya yang tidak bertentangan dengan syariat
Islam.
Sumber dana yang dapat dihimpun dari masyarakat terdiri dari (3) tiga jenis
dana, yaitu:
a. Dana Modal yaitu dana dari pendiri bank dan dari para pemegang saham
tersebut. Modal merupakan dana (dalam bentuk pembeliaan saham) yang
disediakan oleh pemilik yang mempunyai hak untuk memperoleh dividen dan
penggunaan modal yang disertakan tersebut. Dalam perbankan syariah,
mekanisme penyertaan modal pemegang saham dapat dilakukan melalui
musyawarah fi sahm asy-syariqah atau equity participation pada saham
perseroan bank.
b. Dana Titipan Masyarakat baik yang dikelola oleh bank dalam sistem
Wadi‟ah, maupun yang diinvestasikan melelui bank dalam bentuk dana
investasi khusus (Mudhrabah Muqayyadah) atau investasi terbatas
(Mudhrabah Muqayyadah)
3.11 Fungsi Bank Syari’ah
Seperti halnya pada umumnya, bank syari‟ah jiga mempunyai fungsi (kegunaan)
yang sangat penting. Diantara fungsi-fungsi itu antara lain:
1. Memobilisasi tabungan masyarakat, baik domestik maupun asing;
2. Menyalurkan dana tersebut secara efektif ke kegiatan-kegiatan usaha yang
produktif dan menguntungkan secara finansial dengan memperhatikan
keinginan usaha tersebut idak termasuk yang dilarang oleh syari‟ah
102
Universitas Indonesia
3. Melakukan fungsi regulator turut mengatur mekanisme penyaluran dana
kepada masyarakat sesuai dengan kebijakan bank Indonesia, sehingga
dapat mengendalikan aktivitas moneter yang sehat dan terhindar dari
inflasi;
4. Menjembatani keperluan pemanfaatan dana dari pemilik modal dan pihak
yang memerlukan sehingga uang dapat berfungsi untuk melancarkan
perekonomian khususnya dan pembangunan umumnya.
5. Menjaga amanah yang dipercayakan kepadanya sebagai lembaga
keuangan yang berdasarkan prinsip syari‟ah.77
.
3.12 Jenis - jenis Bank Syariah
1. Bank Umum Syariah
2. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR Syariah)
3. Bank Konvensional yang membuka Usaha Syariah ( Cabang Syariah )
77
M ma‟ruf Abdullah, 2006, Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syari’ah di
Indonesia, Banjarmasin: Antasari press, hlm. 104.
102
BAB 4
PERAN PERBANKAN SYARI’AH DALAM PENGELOLAAN WAKAF
UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NO.41 TAHUN 2004 TENTANG
WAKAF
4.1 Dasar Hukum Wakaf Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
Tentang Wakaf
Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang
sebagai sebegai anggota masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib diantara
anggota masyarakat tersebut.1 Hukum tidak sekedar meneguhkan pola-pola yang
ada dalam masyarakat, melainkan ia berusaha untuk menciptakan hal-hal atau
hubungan-hubungan yang baru.2
Peraturan perundang-undangan yang selama ini mengatur masalah
perwakafan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara
lain Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria,
Peraturan Pemerintah (PP) No. 28. Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik,
Peraturan Menteri Agama RI No.1 tahun 1978 tentang Pelaksanaan PP No. 28
Tahun 1977, peraturan Dirjen Bimas Islam Depag RI No. Kep/D/75/1978 dan
Inpres (Intruksi Presiden) RI No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
(KHI), dianggap belum memadai dan masih dianggap menjadi persoalan yang
belum terselesaikan dengan baik, sehingga keinginan kuat dari umat Islam untuk
memaksimalkan peran kelembagaan dalam bidang perwakafan masih mengalami
kendala-kendala formil.
1 Asbar, dkk, Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum, (Jakarta Departemen Agama RI, 2002),
hlm.203
2 Sutjipto Raharjo, Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial bagi Pengembangan Studi Hukum,
Bandung: Alumni, 1977, hlm. 134-145
103
Universitas Indonesia
Pada tanggal 7 Oktober 2004, pemerintah mengeluarkan peraturan baru
tentang wakaf yaitu Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Dengan
berlakunya undang-undang ini, semua peraturan mengenai perwakafan masih
terus berlaku sepenjang tidak bertentangan dengan dan /atau belum diganti dengan
peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini.3 Lahirnya undang-undang
Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf
yang merupakan salah satu instrument dalam membangun kehidupan sosial
ekonomi umat Islam. Undang-undang ini memiliki urgensi, yaitu selain untuk
kepentingan ibadah kehadiran undang-undang wakaf ini juga menjadi momentum
pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial. Sebab
didalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola menejemen
pemberdayaan potensi wakaf secara modern.
Salah satu ketentuan mendasar tentang wakaf yang berhubungan dengan
Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah kelanggengan wakaf.
Dalam peraturan pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
ditetapkan bahwa wakaf bersifat selamanya. Ketentuan yang sama juga terdapat
dalam Kompilasi Hukum Islam. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 ditetapkan bahwa benda wakaf dimanfaatkan untuk selamanya atau
jangka waktu tertentu. Hal ini disebutkan dalam pasal 1 bahwa Wakaf adalah
perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta
benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu
sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan
umum menurut syari‟ah.
Ketentuan didalam undang-undang menyebutkan bahwa wakaf
dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut yaitu: wakif,
nazir,harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka
waktu wakaf. Unsur yang pertama adalah wakif, yaitu pihak yang mewakafkan
harta benda miliknya. Disebutkan didalam bab 2 (dua) dasar-dasar wakaf bagian
keempat Pasal 7 dan 8 mengenai ketentuan wakif, yang menjelaskan bahwa wakif
3 Abdul Ghafur Anshori, Hukum Dan Praktik Perwakafan Di Indonesia, Yogyakarta:
Nuansa Aksara, 2006, hlm. 52.
104
Universitas Indonesia
meliputi baik wakif perseorangan, organisasi dan/atau badan hukum dalam hal ini
merupakan perseorangan warga Negara Indonesia atau warga Negara asing,
organisasi Indonesia atau organisasi asing dan/atau badan hukum Indonesia atau
badan hukum asing.4
Unsur wakaf yang kedua adalah nazhir, yaitu pihak yang menerima harta
benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan
peruntukannya. Dalam PP No.28 maupun KHI hanya mengenal dua macam
nazhir yaitu nazhir perorangan dan nazhir badan hukum, sementara dalam
undang-undang wakaf ditambah lagi nazhir organisasi. Disebutkan dalam pasal 9,
10 dan 11 mengenai ketentuan nazhir, dijelaskan bahwa nazhir meliputi baik
individu, organisasi dan/atau badan hukum dalam hal ini merupakan perseorangan
warga Negara Indonesia, organisasi Indonesia dan atau badan hukum Indonesia.5
Kemudian dijelaskan pula bahwa nazhir perseorangan hanya dapat
menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan sebagai warga Negara Indonesia,
beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan yang
terakhir tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.6 Kemudian untuk nazhir
organisasi hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan sebagai
pengurus organisasi yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan nazhir
perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan organisasi yang bergerak
dibidang sosial, pendidikan kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.7
Dalam menjalankan tugasnya zazhir badan hukum hanya dapat menjadi
zazhir apabila memenuhi persyaratan sebagai pengurus badan hukum yang
bersangkutan dan memenuhi persyaratan zazhir perseorangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dan badan hukum indonesia yang dibentuk sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan badan hukum yang
4 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, pasal 7.
5 Ibid., Pasal 9.
6 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, pasal 10 ayat 1.
7 Ibid., Pasal 10 ayat (2)
105
Universitas Indonesia
bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau
keagamaan Islam.8
Dalam menjalankan tugasnya nazhir mempunyai tugas melakukan
pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta
wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, kemudian mengawasi dan
melindungi harta benda wakaf, sekaligus melaporkan pelaksanaan tugas kepada
Badan Wakaf Indonesia.9 Hal lain yang semakin dilengkapi oleh Undang-Undang
No. 41 Tahun 2004 mengenai imbalan nazhir. Imbalan zazhir yang selama ini
belum secara tegas dibatasi, kini didalam undang-undang dibatasi secara tegas
jumlahnya tidak bolleh lebih dari 10% dari hasil bersih atas pengelolaan dan
pengembangan harta wakaf.
Di dalam ketentuan undang-undang wakaf disebutkan bahwa unsur wakaf
yang ke tiga adalah mengenai harta benda wakaf, dimana harta benda tersebut
yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta
mempunyai nilai ekonomi menurut syari‟ah yang diwakafkan oleh wakif. Adapun
ketentuan baru didalamnya yang berbeda dari beberapa peraturan perundangan
wakaf yang sudah ada adalah sebagai upaya pemberdayaan wakaf secara
produktif dan profesional. Setidaknya undang-undang wakaf sekarang memiliki
substansi penekanan atas benda yang diwakafkan (mauquf bih). Dalam peraturan
perundangan wakaf sebelumnya hanya menyangkut perwakafan benda tidak
bergerak hanya pada wakaf tanah milik, peruntukannya dipergunakan untuk
kepentingan yang tidak produktif, seperti masjid, madrasah, yayasan, tempat
pemakaman dan sebagainya. Sedangkan undang-undang wakaf sekarang ini telah
mengakomodir harta benda wakaf bergerak, seperti uang (cash waqf), saham,
surat-surat berharga dan hak kekayaan intelektual.
Selanjutnya mengenai ikrar wakaf (sebagai unsur wakaf yang ke empat),
yang dimaksud dengan ikrar wakaf (shighat) adalah pernyataan kehendak wakif
yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan
harta benda miliknya. Disebutkan dalam pasal 17 mengenai ikrar wakaf ini bahwa
8 Ibid., Pasal 10 ayat (3)
9 Ibid., Pasal 11
106
Universitas Indonesia
ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir dihadapan Pejabat Pembuat
Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh dua orang saksi.
Unsur wakaf yang kelima dalam undang-undang wakaf adalah mengenai
peruntukan harta benda wakaf. ketentuan tersebut tertuang dalam pasal 22 yang
menyebutkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda
wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi sarana dan kegiatan ibadah; sarana dan
kegiatan pendidikan; bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar yatim piatu,
beasiswa; kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau kemajuan
kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan sysri‟ah dan
peraturan perundang-undangan.10
Selain itu pembahasan mengenai ketentuan pentingnya pendaftaran benda-
benda wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) kepada instansi
yang berwenang. Urgensi pendaftaran benda-benda wakaf itu dimaksudkan agar
seluruh praktik perwakafan dapat dikontrol dengan baik, sehingga bisa dihindari
tindakan penyelewengan yang tidak perlu. Undang-undang ini juga menekankan
pentingnya pemberdayaan benda-benda wakaf. aspek pemberdayaan dan
pengembangan benda wakaf selama ini memang terlihat belum optimal, sehingga
undang-undang wakaf ini menekankan pentingnya pemberdayaan dan
pengembangan benda-benda wakaf yang mempunyai potensi ekonomi tinggi
untuk kesejahtraan masyarakat banyak.11
Sedangkan hal baru yang juga terdapat dalam undang-undang wakaf ini
dan tidak terdapat dalam peraturan sebelumnya adalah menyengkut dibentuknya
badan baru yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI adalah lembaga
independen yang dibentuk oleh pemerintah untuk memajukan dan
mengembangkan perwakafan nasional. BWI berkedudukan di Ibukota Negara dan
dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten atau kota sesuai
dengan kebutuhan. BWI beranggotakan paling sedikit 20 orang dan paling banyak
30 orang yang berasal dari anggota masyarakat. Keanggotaan BWI tersebut
10
Ibid.,Pasal 22.
11 Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya
Progresif Untuk Kesejahtraan Umat, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006., hlm.93.
107
Universitas Indonesia
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden untuk masa jabatan 3tahun. Adapun
tugas dan wewenang BWI adalah sebagai berikut:
1. Melakukan pembinaan terhadap zazhir dalam mengelola dan
mengembangkan harta benda wakaf.
2. Melakukan pengelolaan da n pengembangan harta benda wakaf bersekala
nasional dan internasional.
3. Memberikan persetujuan dan/atau perizinan atas perubahan dan peruntukan
serta status harta benda wakaf.
4. Memberhentikan dan mengganti nahzir.
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam menyusun
kebijakan dibidang perwakafan.
Dilihat dari tugas dan wewenang BWI dalam undang-undang ini nampak
bahwa BWI selain mempunyai tanggungjawab untuk mengembangkan
perwakafan di Indonesia, juga mempunyai tugas untuk membina para nazhir,
sehingga nantinya wakaf dapat berfungsi sebagaimana disyari‟atkannya wakaf
tersebut. Adapun pengawasan terhadap perwakafan pada umumnya dan nazhir
pada umumnya dilakukan oleh pemerintah dibantu badan wakaf atau lembaga
wakaf dari Negara yang bersangkutan.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 56 ayat (1)
menyebutkan bahwa pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah
dan masyarakat, baik aktif maupun pasif. (2) pengawasan aktif dilakukan dengan
melakukan pemeriksaan langsung terhadap nazhir atas pengelolaan wakaf,
sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. (3) pengawasan pasif dilakukan
dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan nazhir
berkaitan dengan pengelolaan wakaf. (4). Dalam melakukan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah dan masyarakat dapat meminta
bantuan jasa akuntan public independen. Dengan ketentuan di atas maka
108
Universitas Indonesia
diharapkan harta wakaf dapat terlindungi serta pengembangannya tetap terjaga
sehingga dapat berfungsi sesuai kehendak wakif.12
Hal berbeda berikutnya yang terdapat dalam undang-undang ini adalah
mengenai cara penyelesaian sengketa. Dalam undang-undang ini penyelesaian
sengketa dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat maupun bantuan pihak
ketiga melalui mediasi, arbitrase dan jalan terakhir adalah pengadilan. Hal ini
berbeda dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya yang menjadikan
pengadilan sebagai jalan utama dalam menyelesaikan sengketa wakaf.
4.2 Peraturan Pengelolaan Wakaf Uang Oleh Bank Syariah Menurut
Undang-Undang Wakaf.
Perbankan merupakan sebuah lembaga yang berfungsi sebagai
penghimpun, pengelola dan penyalur dana masyarakat. Begitu pula yang
dilakukan oleh Perbankan Syari‟ah di Indonesia. Penghimpunan dana yang
diperoleh dari masyarakat dilaksanakan sesuai prinsip syari‟at Islam dan hasilnya
disalurkan untuk kebutuhan umat Islam pada khususnya dan untuk bangsa
Inonesia pada umumnya. Wakaf uang merupakan sebuah lembaga yang relatif
baru dalam dunia Islam di Indonesia yang bertujuan untuk memajukan
kesejahteraan umat. Oleh karena itu diperlukan suatu lembaga profesional yang
dapat mengelola dan mengembangkan wakaf uang agar menjadi suatu hal yang
berguna bagi umat Islam di Indonesia.
Perbankan syari‟ah sebagai suatu lembaga profesional dalam mengelola
dana masyarakat dan dana sosial lainnya seperti dana zakat wakaf dan shadaqah,
perlu juga memperluas usahanya dengan mengembangkan wakaf uang. Oleh
karena itu perbankan harus ambil bagian dalam upaya pengelolaan dan
pengembangan wakaf uang di Indonesia. Dengan dikeluarkannya UU Nomor 41
Tahun 2004, pada tahun 2004 maka sejak saat itu perbankan syari‟ah berperan
besar dalam perkembangan wakaf uang di Indonesia.
12
Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, pasal 56, ayat (1).
109
Universitas Indonesia
Menurut Pasal 28 UU No. 41 Tahun 2004 dinyatakan bahwa wakif dapat
mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syari‟ah
yang ditunjuk oleh Menteri. Jika memperhatikan isi Pasal tersebut, maka lembaga
keuangan syari‟ah memiliki peran terhadap wakaf uang di Indonesia. Yang
dimaksud dengan lembaga keuangan Syari‟ah adalah badan hukum Indonesia
yang bergerak dibidang keuangan syari‟ah.13
Perbankan syari‟ah merupakan
salah satu contoh bentuk lembaga keuangan syari‟ah disamping ada juga asuransi
syari‟ah maupun reksadana syari‟ah. Jika melihat Pasal 28 UU No.41 Tahun 2004
tersebut maka dapat dikatakan bahwa wakif juga dapat mewakafkan benda
bergerak berupa uang melalui perbankan syari‟ah yang ditunjuk oleh menteri.
Sperti yang telah dijelaskan pada Pasal 28 Undang-Undang No. 41 Tahun
2004 bahwa dalam hal ini perbankan syari‟ah memiliki peran terhadap wakaf
uang di Indonesia. Peran seperti apa sebenarnya yang telah dijalankan oleh
perbankan syari‟ah dalam mengembangkan wakaf uang tersebut? Dalam
redaksional Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut,
permasalahan peran perbankan syari‟ah terhadap wakaf uang adalah pada kata
“melalui”. Kata “melalui” ini memiliki banyak penafsiran dan menggambarkan
peran yang sebenarnya dijalankan oleh perbankan syari‟ah terhadap wakaf uang.
Dimana pasal tersebut menyebutkan “ Wakif dapat mewakafkan benda bergerak
berupa uang melalui lembaga keuangan syari‟ah yang di tunjuk oleh Menteri”.
Untuk para wakif sendiri dalam rangka menyetorkan wakaf uang kepada
bank syari‟ah (LKS-PWU) wakif harus mengikuti beberapa prosedur antara lain:14
a. Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
b. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih berupa mata uang asing maka
harus dikonversi terlebih dahulu kedalam rupiah.
c. Wakif harus menyatakan kehendaknya untuk berwakaf uang di LKS-PWU.
d. Wakif menjelaskan asal-usul kepemilikan uang yang akan diwakafkan.
e. Wakif menyetorkan secara tunai dana wakaf ke LKS PWU.
13
Penjelasan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
14 Lihat Peraturan Pemerintah Rebublik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 22.
110
Universitas Indonesia
f. Wakif mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang nantinya akan
dituangkan dalam sertifikat wakaf uang.
g. Apabila wakif tidak dapat hadir ketika menyetorkan dana di LKSPWU,
maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya untuk menggantikan
kehadirannya, dalam hal ini Nazhr tidak perlu hadir pada saat wakif
mewakafkan uangnya, dan
h. LKSPWU akan menanyakan kepada wakif mengenai nazhir mana yang
akan ia pilih untuk mengelola wakaf uangnya.
Secara teknis pelaksanaan tersebut adalah sebagai berikut, setelah wakif
mewakafkan uangnya kepada bank syari‟ah, maka bank syari‟ah akan
menerbitkan dan menyampaikan sertifikat wakaf uang (SWU) kepada wakif dan
nazhir sebagai bukti bahwa penyerahan harta benda wakaf telah
dilakukan.15
Setelah wakif menunjuk nazhir mana yang ia pilih maka nazhir yang
terpilih dapat menempatkan wakaf uang yang ia kelola pada instrumen-instrumen
syari‟ah yang dirasakan menguntungkan, seperti pada tabungan atau deposito.
Namun sebelumnya nazhir harus berkonsultasi dengan bank syari‟ah mengenai
instrumen-instrumen apasaja yang dinilai dapat menguntungkan dari wakaf uang
yang ia kelola mengingat bank syari‟ah saat ini hanya sebagai penitipan wakaf.16
Aturan teknis yang lain menyangkut wakaf uang diatur dalam Pasal 22
Peraturan Pemerintah Tentang Wakaf, dimana wakif wajib:
1. Hadir di LKS-PWU untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya dan
dalam hal wakif tidak hadir maka dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
2. Menjelaskan asal-usul kepemilikan uang yang akan diwakafkan.
3. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU.
4. Mengisi formulir pernyataan kehendaknya yang berfungsi sebagai Akta
Ikrar Wakaf (AIW).
Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama No.4 Tahun 2009 Tentang
Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang (PMA 4/2009) mengatur tentang ikrar
15
Undang-Undang No.30 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 29 ayat (3).
16 Wawancara Mulya E. Siregar, Op.Cit
111
Universitas Indonesia
wakaf yang dlaksanakan oleh wakif kepada nazhir yang dilakukan dihadapan
LKS-PWU atau notaris yang ditunjuk sebagai PPAIW dengan disaksikan oleh dua
orang saksi. Ikrar wakaf tersebut dilakukan setelah wakif menyetorkan wakaf
uang kepada LKS-PWU. Lebih lanjut PMA No.4 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (3),
Pejabat LKS-PWU atau Notaris setelah menerima wakaf uang dari wakif akan
menerbitkan AIW yang memuat sekurang-kurangnya data: (a) nama dan identitas
wakif, (b) nama dan idenbtitas nadzir, (c) nama dan identitas saksi, (d) jumlah
nominal dan asal-usul uang; dan (e) peruntukan dan jangka waktu wakaf. Untuk
itu berdasarkan Pasal 3 PMA No. 4 Tahun 2009 tersebut LKS-PWU wajib
menerbitkan SWU setelah nadzir menyerahkan AIW dan SWU diberikan kepada
wakif dan tembusannya diberikan kepada nadzir.
Adapun beberapa syarat bagi nazhir wakaf uang untuk membuka rekening
dan memperoleh dana wakaf uang dari LKS-PWU adalah:17
a. Menyampaikan permohonan secara tertulis kepada menteri;
b. Melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum;
c. Memiliki kantor operasional di wilayah Rebublik Indonesia;
d. Bergerak dibidang keuangan syari‟ah;
e. Memiliki fungsi menerima titipan (wadi‟ah).
Sementara itu dari segi peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang wakaf yang berkaitan dengan Perbankan Syari‟ah, sampai saat ini
ketentuan yang ada masih terbatas pada peran bank syariah hanya berperan
sebagai lembaga penerima dan penyalur dana wakaf saja yang didasarkan pada
ketentuan perbankan yang berlaku di Indonesia. Ketentuan perbankan dan
kegiatan perbankan yang terkait dengan masalah wakaf antara lain:
1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Bank Umum
Berdasarkan Prinsip Syari‟ah, yang menentukan:
“bank dapat bertindak sebagai baitul maal yaitu menerima dana yang
berasal dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah atau dana sosial lainnya
17
Kementerian Agama Rebublik Indonesia, Op.,Cit, hlm.53
112
Universitas Indonesia
dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan/atau
pinjaman kebajikan (qardhul hasan).18
2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Perkreditan Rakyat
berdasarkan Prinsip Syari‟ah yang menentukan :
“ BPRS dapat bertindak sebagai baitul maal yaitu menerima dana yang
berasal dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf hibah atau dana sosial lainnya
dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan/atau
pinjaman kebajikan (qardhul hasan).19
Sedangkan peraturan Bank Indonesia No. 2/27/PBI/2000 tentang Bank
Umum tidak menyatakan secara eksplisit kegiatan Kantor Cabang Syari‟ah (KCS)
yang berada dibawah Unit Usaha Syari‟ah (UUS) dari Bank Umum Konvensional
yang berkaitan dengan wakaf. namun demikian dengan disebutkannya KCS dapat
melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari‟ah dimaksud sesuai Pasal 1
angka 13 UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah
dengan UU No. 10 Tahun 1998, maka secara implisit KCS dapat pula melakukan
kegiatan yang berhubungan dengan wakaf uang.20
Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia dinyatakan bahwa “ bank
syari‟ah dalam melakukan kegiatan usahanya dapat melakukan kegiatan lain yang
lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syari‟ah Nasional.”21
Disebutkan juga bahwa “BPRS dalam mlakukan kegiatan usahanya dapat
melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan BPRS sepanjang disetujui oleh
Dewan Syari‟ah Nasional.”22
Undang-Undang Perbankan Syari‟ah juga telah mengatur secara tegas
bahwa perbankan syariah sebagai badan sosial diperkenankan menjalankan fungsi
18
Bank Indonesia, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang bank umum
berdasarkan prinsip syari‟ah, SK Dir. BI No. 32/34/KEP/DIR Tahun 1999, Pasal. 29 ayat. 2.
19 Bank Indonesia Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Bank Perkreditan
Rakyat Berdasarkan Prinsip syari‟ah SK Dir. BI No. 32/36/KEP/DIR tahun 1999, Pasal. 28.
20 Siregar et. al, Op.Cit., hlm. 11
21 Bank Indonesia, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Bank Umum
Berdasarkan Prinsip Syari‟ah, Pasal 28 huruf m
22 Bank Indonesia, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Perkreditan
Rakyat Berdasarkan Prinsip Syari‟ah, Pasal 27 huruf c.
113
Universitas Indonesia
sosial sebagai lembaga baitul mal yaitu menerima zakat, infaq, shadaqah, hibah
atau dana sosial yang lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat,
serta saat ini beberapa bank syari‟ah yang telah ditunjuk sebagai LKS-PWU oleh
Kementerian Agama juga berperan menghimpun dana sosial dari wakaf uang dan
menyalurkannya kepada nadzir sebagai kehendak dari wakif.23
Setidaknya ada 4 tujuan bank sebagai pengelola dana wakaf tunai, yaitu:24
a. Menyediakan jasa layanan perbankan dengan menerbitkan sertifikat
wakaf tunai dan melakukan menejemen terhadap wakaf uang tersebut
b. Membantu melakukan mobilisasi tabungan sosial dan melakukan
transformasi dari tabungan sosial ke modal;
c. Memberikan benefit kepada masyarakat khususnya, masyarakat miskin
melalui optimalisasi sumberdaya masyarakat kaya;
d. Membantu perkembangan pasar modal sosial (sosial capital market).
4.3 Beberapa Akad Syari’ah Yang Digunakan Dalam Pengelolaan Wakaf
Uang Agar Dana Pokok Wakaf Tersebut Tidak Berkurang
Dalam rangka mengelola wakaf uang, bank syari‟ah dapat melakukan
berbagai kegiatan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syari‟ah. Menurut
Undang-Undang perbankan yang dimaksud dengan prinsip syari‟ah adalah
“aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk
menyimpan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang
dinyatakan sesuai syari‟ah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil
(mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah),
prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau
pembiayaan berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan
23
Ibid, hlm. 15
24 Kementerian Agama Rebublik Indonesia, Direktorat Jenderal bimbingan Masyarakat
Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia, tahun
2013, hlm. 47
114
Universitas Indonesia
adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank
oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).25
”
Dengan demikian berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan
Perbankan yang telah disebutkan diatas, kegiatan pembiayaan bank syari‟ah
sebagai lembaga keuangan dengan memanfaatkan dana yang berasal dari wakaf
uang bisa berupa pembiayaan dengan prinsip mudharabah musyarakah,
murabahah, ijarah atau ijarah wa iqtina. Berikut ini akan kami terangkan satu
parsatu akad syari‟ah dalam pemanfaatan dana wakaf uang di lembaga perbankan
Syari‟ah.
4.3.1 Al-Mudharabah
Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama
(shahibul maal) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya
menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut
kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila terjadi rugi maka
ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si
pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian
si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.26
Pada sisi mudharabah ini dapat diterapkan untuk:
a. Pembiayaan modal kerja seperti modal kerja perdagangan dan jasa;
b. Investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah, dimana sumber
dana dikelola dengan persayaratan khusus sebagaimana yang telah
ditentukan oleh shahibul maal.27
Dengan demikian melalui pembiayaan dengan prinsip mudharabah bank
syari‟ah dapat memanfaatkan dana yang berasal dari wakaf uang dengan harapan
mendapatkan keuntungan melalui prinsip bagi hasil dimana dana dari keuntungan
bagi hasil itulah yang nantinya akan dibagikan kepada mauquf alaih. Secara teknis
25
Undang-Undang Perbankan, Loc.Cit., Pasal 1 angka 13.
26 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syari‟ah dari Teori Ke Praktik, Cet.1, Jakarta: Gema
Insani Press, 2001, hlm.95.
27 Ibid., hlm.97
115
Universitas Indonesia
operasional, berhubung saat ini praktik pengelolaan wakaf di Indonesia
menempatkan bank syari‟ah sebagai bank kustodi maka dapat kami simulasikan
sebagai berikut:
Setelah wakif mewakafkan uangnya kepada bank syari‟ah, maka bank
syari‟ah akan menerbitkan dan menyampaikan sertifikat wakaf uang (SWU)
kepada wakif dan nazhir sebagai bukti bahwa penyerahan harta benda wakaf telah
dilakukan.28
Setelah wakif menunjuk nazhir mana yang ia pilih maka nazhir yang
terpilih dapat menempatkan wakaf uang yang ia kelola pada instrumen-instrumen
syari‟ah yakni dalam hal ini dengan menggunakan akad mudharabah antara
nazhir dengan mitra kerja bank syariah yang dirasakan menguntungkan, namun
sebelumnya nazhir harus berkonsultasi dengan bank syari‟ah mengenai nasabah
bank syari‟ah yang manakah yang mampu mengelola dana tersebut dan apabila
terjadi keuntungan maka mitra bank syari‟ah tersebut akan menyerahkan
keuntungannya kepada nazhir sesuai akad mudharabah kemudian keuntungan
tersebut oleh nazhir diserahkan kepada mauquf alaih. Namun jika terjadi kerugian
atas pengelolaan dana itu maka akan di tanggung oleh lembaga penjamin
simpanan.
Oleh karena itu prinsip kehati-hatian harus diterapkan dengan cermat oleh
bank syari‟ah sebelum meminjamkan dana yang berasal dari wakaf uang tersebut.
Tentunya lembaga penjamin dalam kegiatan pemanfaatan dana wakaf uang ini
mutlak diperlukan untuk menjaga segala resiko yang terjadi demi memelihara
dana pokok wakaf uang tersebut. Untuk lebih mudah memahaminya lihat skema
berikut ini:
28
Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat., Pasal 29 ayat (3).
116
Universitas Indonesia
4.3.2 Al-Musyarakah
Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha
tertentu dimana masing-masing pihak memberi kontribusi dana atau
(amal/expertise) dengan kesepekatan bahwa keuntungan dan risiko akan
ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.29
Dengan pembiayaan msyarakah ini bank syari‟ah sebagai bank kustodi
akan membantu mengarahkan kepada nazhir untuk menyalurkan dana wakaf yang
tersedia dalam bentuk penyertaan modal kepada mitra perbankan syari‟ah untuk
sebuah proyek investasi. Keuntungan yang diperoleh inilah yang nantinya akan
disalurkan kepada mauquf alaih yang berhak menerima dana dari hasil
pengembangan wakaf uang. Adapun praktiknya sama dengan akad mudharabah
di atas, hanya akad yang dignakan antara nazhir dan nasabah bank syari‟ah yang
berbeda kalau yang sebelumnya menggunakan akad mudharabah maka sekarang
kita menggunakan akad musyarakah yangmana manti antara nasabah bank
syari‟ah dan nazhir wakaf sama-sama mengeluarkan dana untuk bekerjasama
dengan prinsip musyarakah.
29
Ibid., hlm.90.
Terjadi akad mudharabah
Dijamin oleh
Premi
SWU
Ganti Rugi
Wakif Bank Syari’ah Mauquf Alaih
NAZHIR - X
Lembaga Penjamin
Jika Rugi Jika Untung
Dana Wakaf
SWU
Hasil pengelolaan
Nasabah Bank Syari’ah
Wakif m
enu
nju
k
nazh
ir X sam
bil
men
yerahkan
dan
a
wakaf
117
Universitas Indonesia
4.3.3 Al-Murabahah
Al-Murabahah berasal dari kata bahasa Arab Al-ribh (keuntungan), yaitu
akad jual beli antara dua belah pihak dimana pembeli dan penjual menyepakati
harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan
bagi penjual. Nasabah membayar harga barang pada jangka waktu tertentu yang
telah disepakati.30
Adapun arti murabahah secara umum adalah akad jual beli atas barang
tertentu, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian
menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan
sesuai jumlah tertentu. Dalam akad Murabahah, penjual menjual barangnya
dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara
harga jual dengan harga beli barang disebut margin keuntungan.31
Menurut Habib Nazhir dan Hassanuddin didalam Ensiklopedi Ekonomi
dan Perbankan Syariah, murabahah adalah akad jual beli antara bank selaku
penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dari
transaksi tersebut bank mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati
bersama. Atau Murabahah adalah jasa pembiayaan oleh bank melalui transaksi
jual beli dengan nasabah dengan cara cicilan. Dalam hal ini bank membiayai
pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang tersebut
dari pemasok kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan biaya
keuntungan (Cost-Plus Profit) Dan ini dilakukan melalui perundingan terlebih
dahulu antara bank dengan nasabah yang bersangkutan.32
Tidak jauh berbeda dengan pembiayaan-pembiayaan yang telah
diterangkan sebelumnya, dengan dana yang berasal dari wakaf uang, nazhir akan
menyediakan dana dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi yang diminta
nasabah. Jika bank syari‟ah sebagai kustodi maka keuntungan dana wakaf akan
30
http://najae9.blogspot.com/2014/02/bank-konvensional-dan-bank-syariah.html, Bank
Konvensional dan Bank Syari‟ah, diakses 7 juli 2014.
31 Isma‟il, Perbankan Syari‟ah, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 138
32 Menurut Habib Nazhir dan Hassanuddin, Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah,
2004, hlm. 403.
118
Universitas Indonesia
diperoleh nazhir dari tambahan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak atas
pembelian sesuatu barang oleh nazhir yang di sarankan oleh bank syari‟ah.
Keuntungan inilah yang nantinya akan diserahkan kepada mauquf alaih yang
diusahakan akan terus mengalir tanpa mengurangi dana pokok wakaf uang
4.3.4 Al-Ijarah
Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak atas barang atau jasa, melalui
pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan
(ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri.33
Ijarah yakni pemberian
kesempatan kepada penyewa untuk mengambil manfaat dari barang sewaan dalam
jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya sesuai dengan
kesepakatan.34
Akad pembiayaan ijarah dalam rangka pengelolaan wakaf uang ini mirip
dengan pembiayaan leasing dalam bentuk operating lease. Dalam hal ini di akhir
masa al-Ijarah, barang tersebut kembali kepada nazhir (jika peran bank syari‟ah
disini adalah bank kustodi). Jika akad ijarah tersebut dilakukan antara nazhir
dengan nasabah bank syari‟ah dengan hak opsi untuk membeli barang tersebut
maka dipenghujung kerjasama itu barang yang telah disewakan oleh nazhir
menjadi milik nasabah bank syari‟ah. Hal ini dalam akad syari‟ah sering disebut
dengan ijarah mumtahiyyah bittamilik (sewa menyewa yang berakhir menjadi
kepemilikan si penyewa).
Dari berbagai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa potensi dana yang
berasal dari wakaf uang dapat dikelola melalui berbagai produk pembiayaan
sepanjang tidak bertentangan dengan syari‟ah Islam, menurut peneliti dari akad-
akad syari‟ah diatas yang paling produktif untuk digunakan adalah akad al-
murabahah, karena al-murabahah lebih mampu menjamin bahwa dana wakaf
tidak akan berkurang sedikitpun, karena perjanjian keuntungan telah disebutkan
diawal sebagai keuntungan dari pembelian barang.
33
Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syari‟ah dari Teori Ke Praktik, Cet.1, Jakarta: Gema
Insani Press, 2001, hlm. 117
34 Perwataatmaja, Op.Cit., hlm. 29
119
Universitas Indonesia
4.4 Alternatif Peran Perbankan Syari’ah Dalam Pengelolaan Wakaf Uang
Mengenai peran bank syari‟ah dalam pengelolaan wakaf uang, tentu tidak
jauh berbeda dengan yayasan, peran tersebut berhubungan erat dengan posisi
nazhir (pengelola) dengan berbagai variasinya. Menurut E. Mulya Siregar Bank
Syari‟ah mempunyai empat alternatif peran dalam pengelolaan wakaf uang,
yaitu:35
1. Bank syari‟ah sebagai nazhir penerima, penyalur dan pengelola dana
wakaf;
2. Bank Syari‟ah sebagai nazhir penerima dan penyalur dana wakaf;
3. Bank Syari‟ah sebagai pengelola (Fund Manager) dana wakaf;
4. Bank Syari‟ah sebagai kustodi
Untuk lebih jelasnya akan peneliti uraikan sebagai berikut:36
4.4.1 Bank Syari’ah Sebagai Nazhir Penerima, Penyalur dan Pengelola Dana
Wakaf.
Dalam hal ini bank syariah akan mendapat kewenangan penuh untuk
menjadi nazhir wakaf uang. Mulai dari penerima, pengelola dan penyalur dana
wakaf. fungsi bank syari‟ah dalam alternatif pertama ini dapat dikatan sama
dengan yang telah dilakukan oleh SIBL di Bangladesh.
Tanggungjawab penggalangan serta pengelolaan hasil penyaluran dana
wakaf tersebut sepenuhnya ada pada bank syari‟ah. Optimalisasi penggalangan
dana wakaf akan dilakukan dengan memanfaatkan seefektif mungkin kantor dan
divisi pemasaran yang dimiliki oleh bank syari‟ah tersebut. Pengelolaan dana
wakaf akan disertai kerjasama dengan lembaga penjamin untuk memastikan tidak
berkurangnya dana wakaf yang ada pada bank syari‟ah. Sedangkan penyaluran
dana wakaf akan dilakukan dengan mengefektifkan keberadaan jaringan informasi
serta peta distribusi yang dimiliki oleh bank syari‟ah tersebut.
35
Mulya Siregar E, “Peran Perbankan Syari‟ah dalam Wakaf Tunai.” Makalah
disampaikan pada Seminar Sehari Wakaf Tunai Inovasi finansial Islam: peluang dan tantangan
dalam mewujudkan kesejahtraan sosial, jakarta, 10 November 2001.
36 Ibid
120
Universitas Indonesia
Secara tehnis, operasional alternatif pertama ini dimulai dengan adanya
setoran wakif ke bank syari‟ah sebagai dana wakaf. Bank syari‟ah akan
menempatkan dana wakaf tersebut dalam suatu rekening atas nama wakif. Bank
syari‟ah kemudian akan menerbitkan sertifikat wakaf uang sebagai surat
pernyataan penerimaan dana wakaf yang berisikan antara lain nama wakif, alamat,
jumlah dana yang diwakafkan dan sasaran yang telah dipilih oleh wakif (mauquf
alaih) bila ada.
Bank syari‟ah kemudian akan mengelola dana wakaf secara terpisah dengan
dana pihak ketiga lainnya agar bank mudah untuk memantau bahwa dana tersebut
tidak berkurang jumlahnya. Selain itu untuk lebih menjamin bahwa dana wakaf
tidak akan berkurang jumlahnya maka bank syari‟ah wajib berhubungan dengan
lembaga penjamin. Adapun hasil dari wakaf uang tersebut akan dibagikan kepada
sasaran (mauquf alaih) yang telah dipilih wakif atau ditentukan sendiri oleh bank
syari‟ah.37
Untuk lebih jelasnya mari lihat skema berikut ini:
4.4.2 Bank Syari’ah Sebagai Nazhir Penerima dan Penyalur Dana Wakaf
Dalam alternatif yang kedua ini, bank syari‟ah hanya berperan menjadi
nazhir penerima dan penyalur. Sedangkan fungsi pengelolaan dana wakaf akan
dilakukan oleh lembaga lain, misalnya BWN (Badan Wakaf Nasional). Kalau saat
37 Siregar, et al., Op. Cit., hlm 14-15
Dijamin oleh
Ganti Rugi
Wakif Bank syari’ah Mauquf Alaih
Pengelolaan Dana
Lembaga Penjamin
Jika Rugi Jika Untung
Dana Wakaf
SWU
Hasil
Ban
k mem
bayar p
remi
121
Universitas Indonesia
ini dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 sudah dicantumkan mengenai
lembaga Independen yang mengrusi perwakafan di Indonesia, yaitu BWI (Badan
Wakaf Indonesia).38
Dengan demikian tanggungjawab pengelolaan dana wakaf
termasuk hubungan kerjasama dengan lembaga penjamin berada pada BWI.
Dalam alternatif kedua ini, keunggulan Perbankan Syari‟ah berupa adanya
jaringan kantor, jaringan informasi serta peta distribusi digunakan untuk
menggalang dana wakaf maupun untuk menyalurkan hasil pengelolaan dana
wakaf kepada yang berhak. Sedangkan kemampuan profesional perbankan
syari‟ah dalam pengelolaan dana tidak digunakan.
Bila kita lihat prakteknya antara alternatif pertama dengan alternatif kedua
ini hampir sama. Perbedaannya antara keduanya adalah fungsi pengelolaan dana
wakaf tidak dilakukan oleh perbankan syari‟ah. Bank syari‟ah akan menyerahkan
dana wakaf tersebut untuk dikelola oleh lembaga lain, misalnya BWI. Hubungan
atau akad antara bank syari‟ah dengan BWI dapat berdasarkan prinsip ujrah,
dimana bank syari‟ah akan memberikan imbalan kepada BWI atas pengelolaan
dana wakaf yang dilakukan BWI. Untuk menjamin bahwa dana wakaf tidak akan
berkurang jumlahnya maka BWI harus berhubungan dengan suatu lembaga
penjamin. Untuk lebih jelasnya kami gambarkan dengan skema berikut ini:
38
Indonesia (a), Undang-undang tentang pengelolaan zakat, UU No 38,LN. No.164 tahun
1999, LTN. No. 3885, Pasal 1 angka 7.
122
Universitas Indonesia
4.4.3 Bank Syari’ah Sebagai Pengelola Dana Wakaf
Dalam alternatif yang ketiga ini, keunggulan bank syari‟ah berupa
kemampuan secara profesional dalam pengelolaan dana digunakan secara efektif.
Tanggungjawab pengelolaan dana wakaf serta hubungan kerjasama dengan
lembaga penjamin berada pada lembaga Perbankan Syari‟ah. Sedangkan
keunggulan perbankan syari‟ah berupa jaringan kantor dan jaringan informasi
serta peta distribusi, tidak dipergunakan untuk mengoptimalkan penggalangan
dana wakaf dan penyaluran hasil pengelolaan dana wakaf.
Secara tehnis hampir sama dengan alternatif kedua di atas, namun
dalam alternatif ketiga ini posisi bank syari‟ah sebagai penerima dan penyalur
dana wakaf digantikan oleh BWI. Sebaliknya posisi BWI sebagai Pengelola dana
wakaf digantikan oleh bank Syari‟ah. Akad Syari‟ah yang dilakukan antara BWI
dan Bank syari‟ah dapat menggunakan sistim Ujrah, dimana BWI akan
memberikan imbalan kepada Bank Syariah atas pengelolaan dana wakaf tersebut.
Untuk menjamin bahwa dana wakaf tidak berkurang jumlahnya maka bank
Premi
Has
il
Ganti Rugi
Wakif Bank Syari’ah Mauquf Alaih
Pengelolaan Wakaf
Lembaga Penjamin
Jika Rugi Jika Untung
Dana Wakaf
SWU
Hasil
Dan
a Wakaf
Pengelolaan Dana
Dija
min
ole
h
123
Universitas Indonesia
Syari‟ah harus berhubungan dengan suatu lembaga penjamin. Untuk lebih
jelasnya mari kita lihat skema berikut ini:
4.3.4 Bank Syari’ah Sebagai Kustodi.
Berdasarkan Kamus perbankan terbitan Bank Indonesia Tahun 1999,
Kustodian adalah kegiatan penitipan harta untuk kepentingan pihak lain
berdasarkan suatu kontrak; dalam melakukan kegiatan penitipan, baik menerima
titipan harta penitip dengan mengadministrasikannya secara terpisah dari
kekayaan bank; mutasi dari barang titipan yang dilaksanakan oleh bank atas
perintah penitip.39
Dalam UU RI No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana
telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 Pasal 6 huruf I disebutkan bahwa
Bank Umum dapat melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain
berdasarkan suatu kontrak. Lebih jauh sesuai dengan SK Dir. BI No.
32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syari‟ah Pasal 28 ada
beberapa aktifitas kustodi yang bisa dilakukan, yaitu:40
39
Kementerian Agama Rebublik Indonesia, Direktorat Jenderal bimbingan Masyarakat
Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia, tahun
2013, hlm. 51
40 Ibid.,
Dijamin olh
Premi
Has
il
Ganti Rugi
Wakif
Penerima dan
penyalur dana
wakaf Mauquf Alaih
Bank Syari’ah
Lembaga Penjamin
Jika Rugi Jika Untung
Dana Wakaf
SWU
Hasil
Dan
a Wakaf
Pengelolaan Dana
124
Universitas Indonesia
a. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah
berdasarkan prinsip wakalah (huruf e);
b. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahanya untuk
kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip
wakalah (huruf e).
Wakif selaku orang yang berwakaf dapat menyetorkan dananya ke bank
syari‟ah atas nama rekening BWI yang ada di bank syari‟ah tersebut dan akan
mendapatkan sertifikat wakaf tunai. Sertifikat Wakaf Tunai tersebut diterbitkan
oleh BWI dan di titipkan di bank syari‟ah. Sertifikat wakaf tunai tersebut akan
diadministrasikan secara terpisah dari kekayaan bank. Karena bank syari‟ah hanya
berfungsi sebagai kustodi maka tanggungjawab terhadap wakaf terletak pada
BWI. Dana wakaf yang ada di rekening BWI kemudian akan dikelola oleh badan
itu sendiri dan hasil pengelolaan dana diberikan kepada mauquf alaih.
Menurut Mulya E. Siregar Alternatif Peran Perbankan Syari‟ah sebagai
kustodi seperti yang terjadi pada saat ini, karena sebelum berdirinya BWI
alternatif ini diwacanakan untuk mengantisipasi agar Bank Syari‟ah tetap
mendapatkan kesempatan berperan secara optimal dalam wakaf uang. Hal ini
terjadi karena pada saat itu terdapat rencana pemerintah untuk mendirikan BWI
yang bertugas sebagai Nazhir di Indonesia. Jika pemerintah menunjuk Badan
Wakaf untuk berwenang penuh sebagai Nazhir penerima, pengelola sekaligus
penyalur dana wakaf uang, maka perbankan syari‟ah tetap bisa turut serta
berperan dalam hal menjadi kustodi (penitipan) dana wakaf dan menyampaikan
sertifikat Wakaf Uang yang diterbitkan oleh BWI.
Secara tehnis operasional, wakif selaku orang yang berwakaf dapat
menyetorkan dana wakafnya ke bank Syari‟ah atas nama rekening BWI yang ada
di bank syari‟ah tersebut dan sebagai gantinya wakif akan mendapatkan sertifikat
wakaf Uang. Sertifikat wakaf uang tersebut diterbitkan oleh BWI dan dititipkan di
bank Syari‟ah. Sertifikat wakaf uang tersebut akan diadministrasikan secara
terpisah dari kekayaan bank. Karena bank syari‟ah hanya berfungsi sebagai
kustodi, maka tanggungjawab terhadap wakif terletak pada BWI. Dana wakaf
yang ada di rekening BWI kemudian akan dikelola oleh badan itu sendiri dan
hasil pengelolaan dana untuk Mauquf Alaih juga akan disalurkan oleh BWI.
125
Universitas Indonesia
Dalam alternatif ini, keunggulan perbankan syari‟ah berupa kemampuan
mengelola dana, jaringan informasi, dan peta distribusi tidak dimanfaatkan secara
efektif dalam pengelolaan wakaf uang maupun penyalurannya. Sedangkan
keunggulan berupa jaringan kantor masih dapat dimanfaatkan. Untuk lebih
memahami bagaimana praktiknya maka dapat kita lihat skema berikut ini:
Selain ada 4 hal yang telah di jelaskan oleh Mulya E. Siregar masih ada
alternatif lain yang dikenal dengan “Bank Syari‟ah Sebagai Pelaksana
Administrasi Wakaf Uang”. Untuk lebih jelasnya akan kami jabarkan sebagai
berikut:
4.3.5 Bank Syari’ah Sebagai Pelaksana Administrasi Wakaf Uang
Dalam literatur lain ada yang menyebut model ini dengan sebutan Bank
Syari‟ah sebagai kasir Badan Wakaf Indonesia. Intinya dalam alternatif ini peran
bank syari‟ah dalam sangat terbatas. Alternatif ini hampir sama denga alternatif
bank kustodi dalam hal wakif menyetorkan dana wakaf ke bank untuk
dimasukkan ke rekening Badan Wakaf Indonesia. Perbedaanya adalah bank
syari‟ah tidak mengadministrasikan Sertifikat Wakaf Tunai yang diterbitkan oleh
Badan Wakaf Indonesia. Rekening Badan Wakaf Indonesia akan dipelihara oleh
bank syari‟ah sebagaimana layaknya rekening-rekening lainnya yang akan
mendapatkan bonus atau bagi hasil sesuai dengan jenis dan prinsip syari‟ah yang
Dijamin oleh
Premi
SWU
Ganti Rugi
Wakif Bank Syari’ah Mauquf Alaih
Pengelola Wakaf
Lembaga Penjamin
Jika Rugi Jika Untung
Dana Wakaf
SWU
Hasil pengelolaan D
ana W
akaf
Pengelolaan Dana
126
Universitas Indonesia
digunakan (Giro, Wadi‟ah, Tabungan Wadi‟ah atau Tabungan Mudharabah).41
Tanggung jawab terhadap wakif, pengelola dana dan penyaluran dana menjadi
tanggungjawab Badan Wakaf Indonesia. Oleh karena itu badan Wakaflah yang
akan berhubungan dengan lembaga Penjamin untuk menjamin dana wakaf agar
tidak berkurang pokoknya.
Beberapa bank syari‟ah yang menjalankan prinsip ini diantaranya adalah
Bank Mu'amalat Indonesia yang bekerjasama dengan Baitul Maal Muamalat
dalam pengelolaan wakaf uang tersebut. Dalam tehnis operasionalnya bank Bank
Muamalat Indonesia (BMI) melakukan usaha dengan pihak lain sebagai manager
pendayagunaan wakaf (pengelola wakaf) dalam hal ini adalah yayasan Baitul
Maal Mu‟amalat (BMM). Tugas Bank Syari‟ah disini hanya sebatas pihak yang
melakukan administrasi dalam pengumpulan dan penyaluran dana wakaf,
sedangkan untuk kegiatan pengelolaanya menjadi tanggungjawab manager
pendayagunaan dana wakaf (pengelola wakaf).
Dengan demikian secara prinsip peran bank syari‟ah sebagai pelaksana
administrasi atau bank syari‟ah sebagai kasir dana wakaf tidak jauh berbeda
dengan peran bank syari‟ah sebagai penerima dan penyalur dana wakaf. hal ini
mengingat tugas utama bank syari‟ah sebagai pelaksana administrasi/kasir dana
wakaf adalah dalam hal penerimaan dan penyaluran dana wakaf.
Tugas utama dari bank syari‟ah sebagai pelaksana administrasi/kasir dana
wakaf adalah sebagai berikut:42
1. Menerima dana wakaf dan menerbitkan bukti wakaf atas nama pengelola
dana wakaf
2. Mengadministrasikan identitas wakif, jumlah dana yang diwakafkan dan
tujuan penggunaan dana wakaf
3. Mengadministrasikan penyaluran dana wakaf baik infestasi pokok
maupun “keuntungannya”.
4. Menyimpan dana wakaf yang belum tersalurkan
5. Melakukan efaluasi nilai wakaf bersih
41
Ibid.,hlm 52.
42 Pedoman Wakaf Tunai Mu‟amalat “petunjuk pelaksanaan bitul maal mu‟amalat”, hlm.
13-14.
127
Universitas Indonesia
6. Melaporkan hasil aktifitas pengelolaan investasi wakaf kepada wakif.
Sehingga untuk alternatif yang ke-5 ini dapat digambarkan dengan skema
sebagai berikut:
Dari lima alternatif diatas menurut penulis yang paling efektif untuk
diterapkan adalah alternatif pertama yaitu bank syari‟ah sebagai nazir penerima,
penyalur dan pengelola dana wakaf sebagaimana yang telah di praktikkan di
bangladesh, sehingga potensi yang ada di perbankan dapat diterapkan dengan
maksimal dan dana hasil pengelolaan tersebut dapat segera di salurkan kepada
mauquf alaih tanpa melalui banyak perantara.
4.5 Mekanisme Perlindungan Dana Wakaf Oleh Bank Syariah
Perlindungan bagi nasabah/konsumen dalam peraturan bisnis dewasa ini
adalah hal-hal yang sangat penting, dengan adanya perlindungan secara legal akan
menciptakan kenyamanan bagi para pihak yang terkait. Di dalam Undang-Undang
perbankan Nomor 10 tahun 1998, sebagaian besar pasal-pasal yang ada hanya
berkonsentrasi pada aspek-aspak kepentingan perlindungan bank, sehingga
kedudukan nasabah sangat lemah. Baik ditinjau dari kontraktual maupun dalam
bank perjanjian kredit. Dalam hal ini kedudukan nasabah sangat lemah,
Dijamin oleh
Premi
SWU
Ganti Rugi
Wakif BMI Mauquf Alaih
BMM
Lembaga Penjamin
Jika Rugi Jika Untung
Dana Wakaf
SWU
Hasil pengelolaan D
ana W
akaf
Pengelolaan Dana
128
Universitas Indonesia
perjanjian kredit yang biasanya berupa kontrak baku, senantiasa membebani
nasabah debitur dengan berbagai macam kewajiban dan tanggungjawab atas
resiko yang ditimbulkan selama perjanjian berlangsung, sedangkan bank tidak
terkecuali perbankan syariah yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 yang selanjutnya diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Dalam Pasal 6, Pasal 7 da Pasal 13 juga
melakukan hal-hal demikian, padahal kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan
yang sesuai dengan prinsip syari‟ah, sehingga hal-hal seperti ini kiranya harus
mendapat perhatian khusus bagi pemerintah dengan berkoordinasi dengan Dewan
Pengawas Syari‟ah tentunya.
Aturan-aturan dan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Uandang No.
21 tahun 2008 tersebut sangat memberi harapan bagi nasabah, namun dalam
prakteknya sering tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang seharusnya menjadi
dasar dalam operasinya. Banyak kendala yang muncul dalam berlangsungnya
operasional bank syariah seiring dengan perjanjian yang terjadi pada perbankan
secara umum. Seperti klausula eksonerasi43
dalam perjanjian kredit sering
dimanfaatkan bank padahal beban bunga yang tinggi sudah sangat membebani
nasabah . jika diperhatikan dengan seksama beban bank yang tinggi sebenarnya
akan berpengaruh dengan faktor psikologis nasabah, karena bunga menimbulkan
ketidak tenangan dalam usahanya sehingga akan berimbas pada kegagalan usaha
nasabah yang bersangkutan.44
Klausula ekonerasi ini juga terjadi pada aturan dan perUndang-Undangan
pada Bank Syariah, begitu sedikitnya perbedaan praktek yang terjadi dilapangan
dengan bank konvensional, sehingga yang terjadi adalah kerugian besar bagi
nasabah bank syari‟ah, karena hak-hak nasabah bank syari‟ah tersebut kurang
mendapat perhatian dan nilai-nilai perekonomian yang diyakini secara Islam juga
tidak mendapatkan tempat karena sistim etika bisnis secara Islam berbeda dengan
43
Klausula Eksonerasi adalah membebaskan seseorang atau badan usaha dari sebuah
tuntutan atau tanggungjawab. Atau secara sederhana klausula eksonerasi diartikan sebagai klausula
pengecualian kewajiban / tanggungjawab dalam perjanjian.
44 M. Syafi‟i Antonio dan Karen Perwataatmaja, Apa Dan Bagaimana Bank Islam, (jakarta:
Daha Bhakti Wakaf, 1992), hlm. 47
129
Universitas Indonesia
bisnis sekuler atau sistem etika yang telah diusung oleh agama lainnya. Melalui
perkembangan peradaban sistem sekuler mengasumsikan sejumlah kode moralis
yang sangat entropis.45
Karena konsep moral dari sistem etika tersebut berdiri
diatas nilai-nilai temuan manusia seperti halnya epicurianisme atau kebahagiaan
hanya untuk kebahagiaan itu sendiri. Sistem tersebut mengusulkan sistem
perceraian antara etika dengan agama, sedangkan kode moralitas yang diadopsi
selain agama Islam lebih sering menekankan kepada pengkuburan eksistensi
kehidupan manusia dimuka bumi. Dan moralitas etika Islam menanamkan anjuran
akan hubungan manusia dengan tuhannya.46
Dalam melaksanakan bisnis, Umat Islam dituntut untuk melaksanakan
bisnisnya sesuai dengan ketentuan syari‟at. Hal ini didasarkan pada satu kaidah
ushul “ al-aslu fi al afal attaqayyud bihukmi assyar‟i” bahwa hukum asal dari
suatu perbuatan adalah terikat dengan hukum syara‟, maka dalam melaksanakan
suatu bisnis harus senantiasa mematuhi dan tetap berpegang erat pada ketentuan
syari‟ah.47
Dengan kata lain syariah merupakan nilai utama yang menjadi payung
stertegis maupun taktis bagi organisasi bisnis.48
Begitu kokohnya prinsip Islam dalam mengatur bisnis tidak terkecuali
dalam perbankan syari‟ah, maka dari itu terdapat asas-asas dalam al-Qur‟an dan
al-hadits yang dikategorikan sebagai asas perlindungan bagi nasabah di antaranya:
1. Asas pelarangan riba.
2. Asas iktikad baik.
3. Asas kesepakatan.
4. Asas keseimbangan atau keadilan.
5. Asas kebersamaan atau kemitraan.
45
Hukum Entropia: hukum fisika yang menyatakan bahwa setiap materi selalu terkait
dengan ruang dan waktu akan mengalami self destruction (rusak dengan sendirinya), Tarek Al-
diwany, Tarek Al-Diwany, The Problem with Interest, (Jakarta: Akbar Media Aksara, 2005)
dikutip dari Drs. Faisal Badroen dkk, Etika Bisnis Dalam Islam(Jakarta: Prenada Media Group,
2006) cet.I, hlm.67.
46 Ibid, hlm. 68
47 Hukum Syara terdiri atas wajib, sunnah, mubah,makruh dan haram
48 Johan Arifin, Fiqih Perlindungan Konsumen, Semarang: Rasali Semarang, 2007, hlm.37
130
Universitas Indonesia
6. Asas tolong menolong atau persaudaraan.
Maka dari itu kemudian kita temukan beberapa asas yang digunakan dalam
perbankan saat ini, asas-asas tersebut adalah:
1. Asas kesepakatan
2. Asas kehati-hatian
3. Asas non diskriminatif
4. Asas keterbukaan
Dengan demikian asas pelarangan tentang bunga, sistem bagi hasil,
keseimbangan/keadilan, kemitraan/kebersamaan serta asas tolong-menolong
merupakan asas khusus yang dimiliki perbankan berdasarkan prinsip syari‟ah
yang tidak ditemukan pada bank sistem bunga.
4.5.1 Bentuk-Bentuk Perlindungan Nasabah Oleh Bank Syari’ah
Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana di bank, sangat
terkait dengan masalah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.
Lembaga perbankan sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat. Tanpa
kepercayaan dari masyarakat, bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan
usahanya dengan baik. Sehingga tidaklah berlebihan bila dunia perbankan
harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan
memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, terutama
kepentingan nasabah.
Dengan demikian, perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan terhadap
kemungkinan terjadinya kerugian akibat merosotnya kepercayaan
masyarakat, sangat diperlukan.
Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dan bank didasarkan atas
suatu perjanjian. Untuk itu, tentu suatu hal yang wajar apabila kepentingan
dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana
perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada bank. Tidak dapat disangkal
bahwa memang telah ada political will dari pemerintah untuk melindungi
kepentingan nasabah bank, terutama nasabah penyimpan dana. Ini dibuktikan
131
Universitas Indonesia
dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-
Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
4.5.1.1 Perlindungan Tidak Langsung
Perlindungan atau jaminan secara tidak langsung oleh dunia
perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana adalah suatu
perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap
segala resiko kerugian yang timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh
bank. Hal ini adalah suatu upaya dan tindakan pencegahan yang bersifat internal
oleh bank yang bersangkutan dengan melalui hal-hal yang dikemukakan berikut
ini:
4.5.1.2 Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principles)
Ketentuan kehati-hatian pada dasarnya merupakan system pengamanan
umum atas system perbankan secara menyeluruh melalui upaya peningkatan
pengamanan terhadap bank secara individual. Sebagai suatu system pengamanan
umum, diakui bahwa ketentuan kehati-hatian mengandung berbagai pembatasan
terhadap bank secara individual, terutama yang menonjol adalah:
(a) pembatasan terhadap kepentingan individual, dan
(b) Pembatasan keleluasaan.
Karena adanya suatu pembatasan-pembatasan sebagaimana tersebut diatas,
sehingga secara individual menimbulkan suasana yang kurang nyaman. Apabila
pengendalian terhadap pembatasan kepentingan dan atau pembatasan keleluasaan
kurang dapat dikontrol, maka akan terwujud dalam bentuk kecenderungan untuk
menyimpang atau melangar ketentuan yang membatasi tersebut. Demikian pula
yang terjadi dengan ketentuan kehati-hatian di bidang perbankan.
Pasal 2 UU No 10 Tahun 1998 menentukan bahwa Perbankan Indonesia
dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan
menggunakan prinsip kehati-hatian. Dari ketentuan ini, menunjukkan bahwa
prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau
dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip kehati-
hatian tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam
132
Universitas Indonesia
menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti selalu harus konsisten dalam
melaksanakan peraturan perUndang-Undangan di bidang perbankan berdasarkan
profesionalisme dan itikad baik.
Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan Pasal 2 di atas, kita dapat menemukan pasal lain di dalam Undang-
Undang No. 10 Tahun 1998 yang mempertegas kembali mengenai pentingnya
prinsip kehati-hatian itu diterapkan dalam setiap kegiatan usaha bank, yakni
dalam Pasal 29 ayat (2).
Pasal 29 ayat (2) mengemukakan bahwa: Bank wajib memelihara tingkat
kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset,
kualitas manaemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang
berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai
dengan prinsip kehati-hatian.
Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) di atas, maka tidak ada alsan bagi
pihak bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan
kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Ini berarti
bahwa segala perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka melakukan
kegiatan usahanya harus senantiasa berdasarkan kepada peraturan perUndang-
Undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 29 ayat (3) terkandung arti perlunya
diterapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka penyaluran kredit atau pembiayaan
berdasarkan Prinsip Syariah kepada nasabah debitur. Selengkapnya ketentuan
tersebut mengemukakan bahwa:
Pasal 29 ayat (3): Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan
Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh
cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang
memercayakan dananya kepada bank.
Ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) di atas tentu berhubungan erat
dengan ketentuan Pasal 29 ayat (4), karena bertujuan untuk melindungi
kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya. Adapun ketentuan tersebut
menyatakan bahwa:
133
Universitas Indonesia
Pasal 29 ayat (4): Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan
informasi mengenai kemungkinan terjadinya risiko kerugian sehubungan dengan
transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.
4.5.1.3 Batas Maksimum Pemberian Kredit (“BMPK”)
Latar belakang ditetapkannya ketentuan BMPK adalah agar bank
melakukan penyebaran risiko dalam penanaman dananya sedemikian rupa agar
tidak terpusat pada peminjam, kelompok peminjam atau bank sector
tertentu. Konsentrasi pemberian kredit dapat mengakibatkan risiko yang sangat
besar bagi bank. Itulah sebabnya Undang-Undang Perbankan mengatur secara
eksplisit ketentuan BMPK.
Ketentuan BMPK merupakan salah satu ketentuan prudentian banking
yang sangat menentukan kinerja bank, oleh karenanya pengaturan dan ketaatan
terhadap ketentuan BMPK harus menjadi proritas Otoritas Perbankan.
Sebagai salah satu ketentuan prudential banking, ketentuan BMPK
merupakan konsep yang dinamis dalam arti rumusannya dapat disesuaikan dengan
kebutuhan operasional bank dan kepentingan ekonomi nasional. Walaupun
demikian perubahan konsep BMPK jangan sampai dilakukan untuk melakukan
kompromi dengan kondisi pelanggaran yang terjadi maupun digunakan untuk
tujuan non-prudential.
Mengenai Batasan Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)/Legal Lending
Limit) telah diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan
Peraturan Pelaksanaannya.
Pasal 11 ayat (1): Bank Indonesia menetapkan mengenai batas maksimum
pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah,pemberian
jaminan,penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa,yang dapat
dilakukan oleh bank kepada peminjam yang terkait,termasuk kepada perusahaan-
persahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.
Dalam bagian penjelasannya dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan
kelompok (grup) di atas merupakan kumpulan orang atau badan yang satu sama
134
Universitas Indonesia
lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan atau hubungan
keuangan.
Pasal 11 ayat (2): Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
tidak boleh melebihi 30% (tiga perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Menurut penjelasan Pasal 11 ayat (2) di atas, Bank Indonesia dapat
menetapkan batas yang maksimum yang lebih rendah dari 30% (tiga perseratus)
dari modal bank. Pengertian modal bank ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai
dengan pengertian yang digunakan dalam penilaian kesehatan bank. Batas
maksimum yang dimaksud adalah untuk masing-masing peminjam termasuk
perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama.
Pasal 11 ayat (3): Bank Indonesia menetapkan mengenai batas maksimum
pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah,pemberian
jaminan,penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa,yang dapat
dilakukan oleh bank kepada:
a. Pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari
modal disetor bank.
b. Anggota Dewan Komisaris.
c. Anggota Direksi.
d. Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan
huruf c.
e. Pejabat bank lainnya, dan
f. Perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan-
kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hurf
b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
Yang dimaksud dengan keluarga dalam ketentuan Pasal11 ayat (3) adalah
hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis keturunan
lurus maupun ke samping termasuk mertua, menantu, dan ipar.
135
Universitas Indonesia
Pasal 11 ayat (4 A): Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
tidak boleh melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari modal bank yang sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bang Indonesia.
Dalam hal ini, Bank Indonesia dapat menetapkan batas maksimum yang
lebih rendah dari 10% (sepuluh perseratus) dri modal bank. Pengertian modal
bank ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan pengertian yang dipergunakan
dalam penilaian kesehatan bank.
Pasal 11 ayat (4A): Dalam memberikan kredit atau pembiayaan
berdasarkan Prinsip Syariah, bank dilarang melampaui batas maksimum
pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana
diatur dalam ayat (1), ayat(2), ayat(3), dan ayat(4).
Penjelasan ketentuan Pasal 11 ayat (4A) mengemukakan bahwa larangan
ini dimaksudkan agar dalam memberikan kredit atau pembiayaaan berdasarkan
Prinsip Syariah, bank menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat.
Bank dinyatakan melakukan pelanggaran atas ayat ini apabila pada saat
pemberiannya, saldo kredit atau pembiayaan tersebut melampaui batas
maksimum yang ditetapkan Bank Indonesia.
Pasal 11 ayat (5): Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dan ayat (3) wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh
Bank Indonesia.
Dalam bagian penjelasan ketentuan Pasal 11 tersebut dikemukakan, bahwa
pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah oleh bank
mengandung resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga
dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Mengingat, bahwa kredit atau
pembiayaan dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada bank,
resiko yang dihadapi bank dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana
masyarakat tersebut.
Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya
tahannya, bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran kredit
atau pemberian pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan
136
Universitas Indonesia
ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada nasabah
debitur atau kelompok nasabah debitur tertentu.
Berkaitan dengan itu, menurut SK Bank Indonesia No. 31/177/KEP/DIR,
yang dimaksud Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK/Legal Lending Limit)
adalah persentase perbandingan batas maksimum penyediaan dana yang
diperkenankan terhadap modal bank.
Mengenai batas maksimum pemberian kredit tersebut, oleh Bank Indonesia
telah ditetapkan bahwa untuk peminjam atau kelompok peminjam yang
merupakan pihak tidak terkait adalah sebesar 20% dari modal, sedangkan untuk
peminjam atau kelompok peminjam yang terkait adalah 10% dari modal.
Ditetapkannya ketentuan batas maksimum pemberian kredit, baik dalam
UU No. 10 Tahun 1998 maupun peraturan pelaksanaanya semata-mata
bertujuan untuk memelihara kesehatan bank dan meningkatkan daya tahan bank
melalui penebaran risiko dalam bentuk penanaman kredit kepada berbagai
nasabah peminjam. Lebih dari itu, adanya ketentuan batas maksimum pemberian
kredit tersebut untuk mencegah pemberian kredit kepada peminjam atau
kelompok peminjam tertentu saja.
Ketaatan bank dalam melaksanakan ketentuan batas maksimum pemberian
kredit juga merupakan wujud dari kehendak untuk memelihara kesehatan bank
dan wujud perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, tertuama kepentingan
nasabah penyimpan dana pada bank yang bersangkutan.
Ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit sebagaimana
dikemukakan di atas mempunyai kaitan yang erat dengan upaya melindungi
kepentingan nasabah penyimpan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29
ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menentukan
bahwa:
Pasal 29 ayat (3): Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan
Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh
cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang
memercayakan dananya kepada bank.
137
Universitas Indonesia
Ketentuan Pasal 29 ayat (3) di atas menentukan secara tegas, bahwa bank
dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyalur dana dalam bentuk kredit
haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah diatur dalam peraturan
perUndang-Undangan yang berlaku. Hal ini harus dilakukan untuk mencegah
timbulnya kerugian dari nasabah penyimpan dan simpanannya yang ada di bank.
Mengingat, bahwa bank terutama yang bekerja dengan dana dari masyarakat yang
disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, tentu setiap bank perlu terus menjaga
kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya.
4.5.1.4 Kewajiban Mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi
Kewajiban dari bank untuk mengumumkan neraca dan perhitungan laba
rugi diatur dalam Pasal 35 UU No. 10 Tahun 1998. Pasal 35 ini menentukan
bahwa:
Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi dalam waktu
dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Ketentuan tersebut berhubungan erat dengan kewajiban bank untuk
menyampaikan neraca dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya
kepada Bank Indonesia sebagaimana diatur oleh Pasal 34 UU no. 10 Tahun 1998.
Secara lengkap ketentuan Pasal 34 menentukan bahwa:
Pasal 34 ayat (1): Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia
neraca dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya serta laporan
berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Pasal 34 ayat (2): Neraca serta perhitungan laba
rugi tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlebih dahulu diaudit oleh
akuntan publik.
Pasal 34 ayat (3): Tahun buku bank adalah tahun takwim.
Bahwa adanya ketentuan yang mewajibkan bank untuk menyampaikan
dan mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi sebagaimana diatur dalam
Pasal 34 dan 35 di atas, dapat memberikan informasi kepada masyarakat, terutama
138
Universitas Indonesia
nasabah penyimpan mengenai tingkat kesehatan bank dan hal-hal lain yang terkait
dengan bank tersebut.
4.5.1.5 Mengadakan Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank
Banyak alasan dan tujuan dilakukannya merger, akuisisi, dan konsolidasi
oleh pelaku usaha terhadap badan usaha bank yang dimilikinya. Salah satu yang
terpenting adalah untuk meningkatkan efisiensi dan mempertinggi daya saing
perusahaan. Namun demikian, dalam melakukan merger, konsolidasi, dan akuisisi
di bidang perbankan tidaklah dapat dilakukan dengan sebebas-bebasnya, tetapi
dibatasi oleh peraturan perUndang-Undangan yang terkait.
Berkaitan dengan itu, menurut ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No.
28 Tahun 1998 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi bahwa dalam
pelaksanaan merger, konsolidasi, dan akuisisi harus memerhatikan kepentingan
dari semua pihak, yaitu kepentingan bank, kepentingan kreditor, kepentingan
pemegang saham minoritas dan karyawan bank, juga kepentingan rakyat banyak,
dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha bank.
Berdasarkan ketentuan tersebut, jelaslah bahwa dalam rangka pelaksanaan
merger, konsolidasi, dan akuisisi bank kepentingan dari nasabah penyimpan
sebagai kreditor telah memperoleh perlindungan hukum.
4.5.1.6 Melindungi Nasabah Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan
Konsumen
Dalam kegiatan perbankan, nasabah bank dapat dikatakan sebagai
konsumen. Menurut Undang-Undang No. 8/1999, konsumen didefinisikan
sebagai “setiap orang pemakai dan/atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat,..” Sementara konsumen sebagai nasabah bank dapat dibedakan
sebagai kreditur (dalam hal penyimpanan uang melalui tabungan atau deposito)
dan sebagai debitur (dalam hal nasabah melakukan pinjaman uang kepada bank).
139
Universitas Indonesia
4.6 Perlindungan Hukum Terhadap Dana Wakaf Melalui Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS)
4.6.1 Peranan LPS Dalam Melindungi Nasabah
Perbankan mempunyai peran yang penting dalam sistim perekonomian.
Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan perlu diperkuat. Untuk itu perlu
diberikan jaminan atas dana yang disimpannya. Keberadaan sistem penjamin
simpanan yang diatur secara tegas dan disusun secara lengkap dapat
meningkatkan kepercayaan dan pada akhirnya memperkuat sistem perbankan.
Untuk menigkatkan kepercayaan tersebut, banyak negara memberikan
perlindungan kepada nasabahnya dengan menerapkan suatu sistem pejamin
simpanan (deposit protection system) dalam bentuksisitem penjaminan nasabah
yang ditentukan secara eksplisit49
Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga yang independen,
transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.50
Penjaminan simpanan nasabah bank yang diharapkan dapat memelihara
kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimumkan
risiko yang membebani anggaran negara atau risiko yang menimbulkan moral
hazard.51
Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan tidak terlepas dari fungsinya yang
sangat penting. Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan adalah : 52
a. Menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan
b. Turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan
kewenangannya
Dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan
kewenangannya, Lembaga Penjamin Simpanan akan melakukan penyelesaian atau
49
Gillian GH Garcia (1), “Deposit Insurance: Obtaining the Benafit and Avoiding the
Pitfalls”, IMF, (Wasinton DC, 1996),hal.2
50 Undang-Undang LPS, Tahun 2004, Pasal 2.
51 Penjelasan Undang-Undang No. 24 tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan
52 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan
140
Universitas Indonesia
penanganan bank gagal. Bank gagal (failing bank) adalah bank yang mengalami
kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan
tidak dapat lagi disehatkan oleh Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) sesuai
dengan kewenangan yang dimilikinya. Lembaga Pengawas Perbankan adalah
Bank Indonesia atau Lembaga Pengawas sektor jasa keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia. Apabila kondisi bank
yang mengalami kesulitan keuangan tersebut semakin memburuk, antara lain
ditandai dengan menurunnya tingkat solvabilitas bank, tindakan penyesaian dan
penanganan lain harus segera dilakukan.53
Dalam menghadapi menurunnya tingkat solvabilitas bank, penyelesaian
dan penanganan Bank yang gagal diserahkan kepada Lembaga Penjamin
Simpanan yang akan bekerja setelah terlebih dahulu dipertimbangkan perkiraan
dampak pencabutan izin usaha bank tehadap perekonomian nasional.54
Apabila pencabutan izin usaha bank diperkirakan memiliki dampak
terhadap perekonomian nasional, tindakan penanganan yang dilakukan oleh
Lembaga Penjamin Simpanan didasarkan pada keputusan komite koordinasi.
Mengingat fungsinya yang penting tersebut maka Lembaga Penjamin Simpanan
harus independen, transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan
wewenangnya. Oleh karena itu status hukum “governance” pengelolaan
kekayaan, kewajiban dan akuntabilitas Lembaga Penjamin Simpanan serta
hubungannya dengan organisasi lain perlu diatur secara tegas dalam peraturan
perUndang-Undangan. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
Pengertian tentang independensi bagi Lembaga Penjamin Simpanan
mengandung arti bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Lembaga
Penjamin Simpanan tidak bisa dicampurtangani oleh pihak manapun termasuk
53
Penjelasan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan
54 Ibid
141
Universitas Indonesia
oleh pemerintah kecuali atas hal-hal yang ditanyakan secara jelas di dalam
Undang-Undang ini.55
Dalam menjalankan fingsinya, Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai
tugas-tugas yang meliputi :
a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaanpenjamin simpanan.
b. Melaksanakan penjamin simpanan.
Untuk lebih terperinci tugas yang dapat dilakukan Lembaga Penjamin
Simpanan sehubungan dengan menjalankan fungsinya adalah sebagai berikut :56
a. Merumuskan dan menetepkan kebijakakn dalam rangka turut aktif memelihara
stabilitas sistem perbankan;
b. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank
Gagal (bank resolution) yang tidak berdampak sistemik; dan
c. Melaksakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.
Dalam rangka melaksanakan tugas Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai
wewenang sebagai berikut :57
a. Menetapkan dan memungut premi penjaminan;
b. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali
menjadi peserta;
c. Melakukan pengeloaan kekayaan dan kewajiban Lembaga Penjamin
Simpanan
d. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan
keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak
melanggar kerahasiaan bank;
e. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data
sebagaimana dimaksud pada huruf d;
f. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;
55
Penjelasan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Pemjamin Simpanan
Pasal 2 ayat 3
56 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Pasal 5
57 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Pasal 6
142
Universitas Indonesia
g. Menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak
bagi kepentingan dan/atau atas nama Lembaga Penjamin Simpanan, guna
melaksanakan sebagian tugas tertentu;
h. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan
simpanan; dan
i. Menjatuhkan sanksi administratif.
Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan penyelesaian dan
penanganan Bank Gagal dengan kewenangan:
a. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang
saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
b. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang di
selamatkan;
c. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap
kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak
ketigayangg merugikan bank; dan
d. Menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur
dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.
Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Lembaga Penjamin Sipanan
Dapat meminta data, informasi, dan/atau dokumen kepada pihak lain. Setiap pihak
yang dimintai data, informasi, dan/atau dokumen wajib memberikannya kepada
Lembaga Penjamin Simpanan.
4.6.2 Pihak Yang Terlibat Dalam Lembaga Penjamin Simpanan
Seluruh Bank umum yang berbadan hukum Indonesia diwajibkan untuk
menjadi anggota LPS begitu juga dengan cabang bank asing yang melakukan
kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta
Penjaminan. Bank peserta penjaminan meliputi seluruh Bank Umum (termasuk
kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan
kegiatan perbankan dalam wilayah Republik Indonesia) dan Bank Perkreditan
Rakyat, baik bank konvensional maupun bank berdasarkan prinsip syariah.
Sedangkan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di Indonesia yang
143
Universitas Indonesia
melakukan kegiatan perbankan di luar wilayah Republik Indonesia tidak termasuk
dalam Penjaminan.58
Organ Lembaga Penjamin Simpanan terdiri dari Kepala
Eksekutif dan dewan Komisioner. Kepala Eksekutif dibantu oleh sebanyak-
banyaknya 5 (lima) orang direktur. Direktur diangkat dan diberhentikan oleh
dewan Komisioner.59
Dewan Komisioner adalah organ tertinggi dalam Lembaga
Penjamin Simpanan.60
Keputusan dewan komisioner adalah keputusan yang
ditetapkan oleh dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan yang memuat
aturan intern.
Selain Lembaga Penjamin Simpanan itu sendiri, para pihak dalam
Lembaga Penjamin Simpanan tidak terlepas dari masalah kepesertaan didalam
Lembaga Penjamin Simpanan. Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha
diwilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi pesrta Penjamin. Kewajiban
bank menjadi peserta Penjamin tidak termasuk Badan kredit Desa.
Seluruh bank umum yang berbadan hukum Indonesia sebaiknya memang
menjadi anggota Lembaga Penjamin Simpanan. Hal ini dimaksudkan untuk
mengurangi adverse selection, yang dalam hal ini hanya bank yang lemah yang
mau menjadi anggota. Kewajiban menjadi anggota LPS ini tidak lain adalah untuk
penjaminan simpanan. Terutama bagi bank yang lemah.
Secara khusus penjamin tidak membolehkan anggotanya untuk keluar dari
keanggotaan. Meskipun sistem keanggotaan wajib menimbulkan subsidi silang
dari bank yang kuat kepada bank yang lemah, namun seluruh bank menikmati
keuntungan dengan adanya stabilitas industri perbankan. Untuk bank yang kuat
harus diwajibkan membayar stabilitas yang dinikmati tersebut.
Selain bank nasional, cabang bank asing juga harus diwajibkan menjadi
anggota. Kantor cabang bank asing tersebut diwajibkan membayar premi asuransi
sebagai biaya dalam melakukan bisnis di Indonesia. Bagaimanapun simpanan
58
Zulkarnaen Sitompul, Lembaga Penjamin Simpanan Substansi dan
Permasalahan,(Jakarta: Books Terrace & Library, 2007), hal.227
59 Undang-Undang LPS Tahun 2004 Pasal 62.
60 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Pasal 1
144
Universitas Indonesia
yang dijamin pada kantor cabang bank asing tersebut adalah simpanan milik
warga negara dan atau penduduk Indonesia.
Cabang bank nasional yang beroperasi di luar negeri seharusnya tidak
dicakup oleh penjamin simpanan. Hal ini didasarkan pada tujuan dari dibentuknya
Lembaga Penjamin Simpanan, yaitu untuk melindungi penduduk domestik, bukan
asing.
Bagi bank perkreditan rakyat sebaiknya dibuat skim penjamin tersendiri.
Hal ini mengingat karakteristik khusus yang dimiliki oleh Bank Perkreditan
Rakayat (BPR). Selama ini program penjaminan pemerintah untuk BPR
ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang
jaminan terhadap kewajiban pembayaran BPR. Keputusan Presiden tersebut
dijabarkan lebih lanjut melalui Surat Keputusan Direksi BI noor 31/166/KEP/Dir
tanggal 1 Desember 1998 tentang persyaratan dan tata cara Penjaminan
Pemerintah terhadap kewajiban Pembayaran BPR dan SK Dir BI No.
31/167/KEP/DIR tanggal 1 Desember 1998 tentang persyaratan dan tata cara
Penjaminan Pemerintah terhadap kewajiban Pembayaran BPR Syariah.61
Dalam ketentuan untuk BPR secara tegas menyebutkan jenis-jenis
simpanan yang dijamin Pemerintah. Pembayaran jaminan Pemerintah terhadap
simpanan pihak ketiga dilakukan setelah Bank Indonesia membekukan kegiatan
usaha BPR dan pelaksanaan pembayarannya dilakukan oleh bank pembayar.
Bekerjanya Lembaga Penjamin Simpanan tidak terlepas dari lembaga-
lembaga lain seperti Lembaga Pengawas Perbankan, Bank Indonesia dan Komite
Koordinasi.62
Lembaga Penjamin Simpanan melakukan tindakan penyelesaian atau
penanganan bank yang mengalami kesulitan keuangan dalam kerangka
mekanisme kerja yang terpadu, efisien dan efektif untuk menciptakan ketahanan
sektor keuangan Indonesia. Lembaga Penjamin Simpanan bersama dengan
61
Marulak Perdede, “Perspektif Perlindungan Hukum Simpanan Dana Nasabah pada
Bank”, Jurnal Hukumj Bisnis Volume 11, 2000, hal 53.
62 Bagian Umum Penjelasan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga
Penjamin Simpnan
145
Universitas Indonesia
Menteri Keungan, Bank Indonesia dan Lembaga Pengawas Perbankan menjadi
anggota Komite Koordinasi.63
Lembaga pengawas Perbankan adalah Bank Indonesia atau lembaga
pengawasan sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksuk dalam Undang-Undang
tentang Bank Indonesia.
Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana
dimaksuk dalam Undang-Undang tentang bank Indonesia. Kewenangan bank
Sentral dalam melakukan pegaturan dan pengawasan bank adalah sebagi alat atau
sarana untuk mewujudkan system perbankan yang sehat, yang menjamin dan
memastikan dilaksanakan segala peraturan perUndang-Undangan yang terkait
dalam penyelenggaraan usaha bank oleh bank yang bersangkutan.
Pengawasan tehadap bank oleh Bank Indonesia sebagai bank Sentral dapat
bersifat pengawasan langsung atau pengawasan tidak langsung. Menurut
penjelasan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang
Bank Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan pengawasan langsung adalah
dalam bentuk pemeriksaan yang disertai dengan tindakan-tindakan perbaikan.
Sedangkan yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung terutama dalam
bentuk pengawasan dini melului penelitian, analisis dan evaluasi laporan bank.
Berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan bank, pada dasarnya hal-hal
yang dapat dilakukan oleh otoritas pengasasan meliputi 4 kewenangan yaitu
kewenangan membrikan izin (power to license), kewenangan untuk
mengatur (power to regulate), kewenangan untuk mengendalikan atau
mengawasi (power of control), dan kewenangan untuk menegakkan sanksi (power
to impose senction).
Komite koordinasi adalah komite yang beranggotakan Menteri Keuangan,
LPP, bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan yang memutuskan
kebijakan penyelesaian dan penanganan suatu Bank Gagal yang ditengarai
berdampak sistematik.
63
Ibid
146
Universitas Indonesia
Dalam menjalankan tugasnya, Lembaga Penjamin Simpanan dapat bekerja
sama dengan organisasi atau lembag dalam negri. Lembaga Penjamin Simpanan
dapat bertindak sebagai anggota dari organisasi atau lembaga internasional
mewakili Negara republik Indonesia apabila terdapat ketentuan bahwa anggota
dan organisasi atau lembaga internasional tersebut mengharuskan atas nama
negara.
4.6.3 Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Lembaga Penjamin Simpanan.
LPS berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut
aktif dalam memelihara system perbankan sesuai dengan kewenangannya.
LPS bertugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan
penjaminan simpanan, melaksanankan penjaminan simpanan, Merumuskan dan
menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem
perbankan, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian
Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik, dan melaksanakan penanganan Bank
Gagal yang berdampak sistemik.
LPS berwenang untuk menetapkan dan memungut premi penjaminan,
menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi
peserta, melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS, mendapatkan data
simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil
pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank, melakukan
rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data tersebut pada angka 4,
menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim, menunjuk,
menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan
dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu, melakukan
penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan, dan
menjatuhkan sanksi administratif. Simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito,
sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu,
yang berasal dari masyarakat, termasuk yang berasal dari bank lain, Nilai
simpanan yang dijamin LPS mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha
147
Universitas Indonesia
bank.64
Defenisi simpanan dalam Undang-Undang Perbankan tahun 1998 Pasal 1
angka 7 menetapkan bahwa:
Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank
berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat
deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan untuk itu.
Selanjutnya dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10m Tahun 1998
dijelaskan pula bahwa : Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan
setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran
lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada
waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Sertifikat
deposito adalah simpanan dalam bentuk depositoyang sertifikat bukti
penyimpanannya dapat dipindahtangankan. Sedang Tabungan adalah simpanan
yang penarikannya hany dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati,
tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang
dipersamakan dengan itu.
Bank yang manjadi anggota Lembaga Penjamin Simpnan maupun lembaga
itu sendiri bersama-sama bertanggung jawab mempublikasikan simpanan yang
dijamin dan yang tidak dijamin. Masyarakat berhak mengetahui hal tersebut untuk
melindungi kepentingan mereka. Cakupan penjaminan harus diberitahukan
terlebih dahulu dan tidak dapat diinterpretasikan setelah terjadi kebangkrutan.
Dalam setiap dokumen simpanan harus dicantumkan apakah simpanan
tersebut dijamin oleh penjamin sipanan atau tidak. Mewajbkan lembaga keuangan
non bank memberitahukan bahwa simpanan atau instrumen lain yang mereka
tawarkan tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan merupakan suatu
kebijaksanaan yang perlu dipertimbangkan.
64
Krisna Wijaya, PenjaminaSimpanan dan Stabilitas Perbankan,
http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub_id=30, dikutip dari Maclachan, Fiona
C, Market Discipline in Bank Regulation; Panecea or Paradox, The Independent Review VI, n Fall
2001
148
Universitas Indonesia
Bank yang menjadi Lembaga Penjamin Simpanan maupun lembaga itu
sendiri bersama-sama bertanggung jawab mempublikasikan simpanan yang
dijamin dan tidak dijamin. Masyarakat berhak mengetahui hal tersebut untuk
melindungi kepentingan mereka. Cakupan penjaminan harus diberitahukan
terlebih dahulu dan tidak dapat diintegrasikan setelah terjadi kebangkrutan.
Dalam setiap dokumen simpanan hasus dicantumkan apakah simpanan
tersebut dijamin oleh penjamin simpanan dicantumkan apakah simpanan tersebut
dijamin oleh penjamin simpanan atau tidak. Mewajibkan lembaga keuangan non
bank memberitahukan bahwa simpanan atau instrumen lain yang mereka
tawarkan tidak dijamin oleh lembaga penjamin simpanan merupakan suatu
kebijaksanaan yang perlu dipertimbangkan.
Dalam kaitannya dengan kebangkrutan bank, penjamin simpanan akan
berperan sebagai kreditur terbesar dari bank tersebut. Dengan demikian penjamin
simpanan memiliki kepentingan sangat besar terhadap penyelamatan kekayaan
bank yang bangkrut tersebut. Begitu suatu bank dicabut ijin usahanya harus
dengan segera menempatkan penjamin simpanan sebagai kurator. Di Indonesia
Pasal 37 ayat (2) (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 meneptakan :
Apabila menurut penelitian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat
membahayakan system perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin
usaha dan memerintahkan direksi Bank untuk segera menyelenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk
tim likuidasi.
Selanjutnya ayat (3) Pasal tersebut menetapkan :
Dalam hal Direksi Bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada
pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum
bank, penunjukkan tim likuidasi dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan
peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
Dengan didirikannya Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia ketentuan
tersebut di atas harus siubah dengan mewajibkan bank Indonesia atau lembaga
149
Universitas Indonesia
yang berwenang mencabut izin usaha bank, agar segera menunjuk Lembaga
Penjamin Simpanan sebagai kurator.
Sebagai kurator bank yang di likuidasi, lembaga penjamin simpanan perlu
diberikan kedudukan utama dalam memperoleh asset bank. Undang-Undang
perbankan yang berlaku tidak mengatur kedudukan hukum dari nasabah
penyimpan terhadap asset bank yang dilikuidasi. Kedudukan hukum nasabah
penyimpan tersebut hanya diatur dalam tingkat peraturan pemerintah dimana
kedudukan nasabah berada pada urutan setelah gaji pegawai yang terutang, biaya
perkara dipengadilan, biaya lelang yang terutang, pajak yang terutang yang berupa
pajak bank dan pajak yang dipungut oleh bank selaku pemotong pemungut pajak
dan biaya kurator.65
Untuk memberikan kedudukan yang kuat bagi lembaga penjamin
simpanan perlu ditegaskan dalam Undang-Undang bahwa nasabah penyimpan
memiliki kedudukan utama terhadap aset bank yang dilikuidasi. Dengan demikian
Penjamin Simpanan telah melakukan pembayaran, maka penjamin simpanan akan
memperoleh kedudukan sebagai pemegang hak utama. Pergantian ini adalah apa
yang dalam hukum perjanjian dinamakan subrogasi.
Jaminan hukum yang diberikan oleh bank terhadap nasabah penyimpan dana
dapat dilihat dari aspek kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan serta hak-hak
yang ditetapkan oleh hukum bagi bank terhadap para nasabah, serta mengenai
sanksi-sanksi huku yang dapat dijatuhkan kepada bank yang tidak mematuhi
kewajiban-kewajibannya dan melanggar larangan-larangan itu, baik karena
ketidak patuhan dan pelanggaran itu , telah menimbulkan kerugian bagi para
nasabah penyimpan dana. Sanksi hukum yang dapat dikenakan dapat berupa
sanksi administratip terhadap bank itu dan terhadap pengelolaannya (anggota
dewan komisaris, dereksi dan pegawai bank). Sanksi perdata dan sanksi pidana
yang dapat diputuskan oleh pengadilan terhadap pengelola bank itu.
65
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan izin usaha,
Pembubaran dan Likuidasi Bank Pasal 17 ayat (1)
150
Universitas Indonesia
4.7 Simpanan Yang Dijamin Oleh LPS66
1. Simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito, sertifikat deposito
tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
2. Simpanan nasaban Bank Berdasarkan Prinsip Syari‟ah yang dijamin
melipti:
a. Giro berdasarkan Prinsip Wadi‟ah;
b. Giro berdasarkan Prinsip Mudharabah;
c. Tabungan berdasarkan Prinsip Wadi‟ah;
d. Tabungan berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah atau
berdasarkan prinsip mudharabah muqayyadah yang risikonya
ditanggung oleh bank
e. Deposito berdasarkan Prinsip Mudharabah muthlaqah atau berdasarkan
prinsip mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh
bank; dan/atau
f. Simpanan berdasarkan Prinsip Syari‟ah lainnya yang ditetapkan oleh
LPS setelah mendapat pertimbangan LPP
3. Simpanan yang dijamin mencakup pula simpanan yang berasal dari bank
lain.
4. Nilai simpanan yang dijamin LPS merupakan saldo pada tanggal
pencabutan izin usaha Bank
5. Saldo tersebut berupa:
a. Pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah, untuk
simpanan yang memiliki komponen bagi hasil yang timbul dari
transaksi dengan prinsip syari‟ah;
b. Pokok ditambah bunga yang telah menjadi hak nasabah, untuk
simpanan yang memiliki komponen bunga;
c. Nilai sekarang per tanggal pencabutan izin usaha dengan
menggunakan tingkat diskonto yang tercatat pada bilyet, untuk
simpanan yang memiliki komponen diskonto.
66
http://www1.lps.go.id/in/web/guest/simpanan-yang-dijamin;jsessionid, Simpanan Yang
Dijamin Oleh Lemnaga Penjamin Simpanan (LPS), diakses 27 Juni 2014.
151
Universitas Indonesia
6. Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada bank adalah hasil
penjumlahan saldo seluruh rekening simpanan pada bank tersebut, baik
rekening tunggal maupun rekening gabungan (joint account);
7. Untuk rekening gabungan (joint account), saldo rekening yang
diperhitungkan bagi satu nasabah adalah saldo rekening gabungan tersebut
yang dibagi secara prorata dengan jumlah pemilik rekening.
8. Dalam hal nasabah memiliki rekening tunggal dan rekening gabungan
(joint account), saldo rekening yang terlebih dahulu diperhitungkan adalah
saldo rekening tunggal.
9. Dalam hal nasabah memiliki rekening yang dinyatakan secara tertulis
diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain (beneficiary), maka saldo
rekening tersebut diperhitungkan sebagai saldo rekening pihak lain
(beneficiary) yang bersangkutan
10. Sejak 13 Oktober 2008, saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu
bank adalah paling banyak sebesar Rp 2 Milyar
Berdasarkan ketentuan di atas, maka konsep wakaf uang yang dana pokoknya
tidak boleh berkurang sedikitpun hanya dapat dilindungi oleh LPS maksimal
sebesar 2 Miliar, sehingga jika dana wakaf yang dikelola oleh nazhir wakaf uang
lebih dari 2 Miliar maka selebihnya dari 2 Miliar tersebut tidak akan dilindungi
oleh LPS jika terjadi suatu risiko. Untuk mengantisipasi hal ini tentunya
pemerintah harus membuat peraturan perUndang-Undangan khusus menyangkut
perlindungan dana wakaf uang, sehingga konsep wakaf uang yang saat ini telah
diataur didalam Undang-Undang No. 41/2004 dapat diterapkan dengan baik.
4.8 Analisis Terhadap Peraturan-Peraturan Perbankan Syari’ah Dalam
Pengelolaan Wakaf Uang
Dari beberapa ketentuan diatas, peran bank syari‟ah sebagai pengelola
dana wakaf tidak disebutkan secara eksplisit dalam peraturan perundang-
undangan, namun pada kenyataanya bank syari‟ah dapat mengambil peran sebagai
penerima dan penyalur dana wakaf sejak sebelum diundangkannya Undang-
Undang Wakaf. seperti yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI)
152
Universitas Indonesia
yang menjalin kerjasama dengan Yayasan Baitul Maal Muamalat dalam
mengelola wakaf uang. Wewenang pengelolaan ini dipandang penting karena
berbeda dengan dana sosial lainnya seperti zakat, infaq dan shadaqah, dana wakaf
tidak dapat dibagikan langsung kepada orang yang berhak, melainkan harus
dikelola terlebih dahulu baru kemudian hasilnya dapat dibagikan kepada yang
berhak.67
Dalam surat keputusan direksi Bank Indonesia dinyatakan bahwa “ bank
syari‟ah dalam melakukan kegiatan usahanya dapat melakukan kegiatan lain yang
lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syari‟ah Nasional.”68
Disebutkan juga bahwa “BPRS dalam mlakukan kegiatan usahanya dapat
melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan BPRS sepanjang disetujui oleh
Dewan Syari‟ah Nasional.”69
Apabila kata “kegiatan lain” dalam dua pasal di atas diartikan sebagai
kegiatan pengelolaan wakaf, maka sebenarnya secara implisit bank syari‟ah dapat
bertindak menjadi pengelola wakaf, tinggal sekarang yang masih menjadi masalah
adalah bagaimana agar Dewan Syari‟ah Nasional mengeluarkan fatwa yang
membolehkan Bank Syari‟ah bertindak sebagai pengelola dana wakaf. terlebih
karena sebelumnya majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang
membolehkan praktik wakaf uang di Indonesia.
Walaupun demikian, apabila ketentuan tersebut tetap dianggap belum bisa
menjadi dasar hukum yang cukup bagi perbankan syari‟ah untuk menjadi Nazhir
wakaf, maka penyempurnaan ketentuan yang menyatakan secara eksplisit harus
dilakukan oleh pemerintah dan DPR untuk bersama-sama membuat peraturan
perundang-undangan agar bank syari‟ah diberi kepercayaan sebagai nazhir wakaf
uang yaitu dengan mewujudkan Undang-Undang.
Unsur wakaf yang berkaitan dengan bank syari‟ah adalah nazhir, yaitu
pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan
67
Ibid., hlm. 11
68 Bank Indonesia, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR/1999
Tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari‟ah, Pasal 28 huruf m
69Bank Indonesia, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999
Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syari‟ah, Pasal 27 huruf c.
153
Universitas Indonesia
dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Dalam PP No.28 maupun KHI
hanya mengenal dua macam nazhir yaitu nazhir perorangan dan nazhir badan
hukum, sementara dalam undang-undang wakaf ditambah lagi nazhir organisasi.
Disebutkan dalam pasal 9, 10 dan 11 mengenai ketentuan nazhir, dijelaskan
bahwa nazhir meliputi baik individu, organisasi dan/atau badan hukum dalam hal
ini merupakan perseorangan warga Negara Indonesia, organisasi Indonesia dan
atau badan hukum Indonesia.70
Kemudian dijelaskan pula bahwa nazhir perseorangan hanya dapat
menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan sebagai warga Negara Indonesia,
beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan yang
terakhir tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.71
Kemudian untuk nazhir
organisasi hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan sebagai
pengurus organisasi yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan nazhir
perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan organisasi yang bergerak
dibidang sosial, pendidikan kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.72
Dalam menjalankan tugasnya zazhir badan hukum hanya dapat menjadi
zazhir apabila memenuhi persyaratan sebagai pengurus badan hukum yang
bersangkutan dan memenuhi persyaratan zazhir perseorangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dan badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan badan hukum yang
bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau
keagamaan Islam.73
Dalam menjalankan tugasnya nazhir mempunyai tugas melakukan
pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta
wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, kemudian mengawasi dan
melindungi harta benda wakaf, sekaligus melaporkan pelaksanaan tugas kepada
70
Ibid., Pasal 9.
71 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, pasal 10 ayat 1.
72 Ibid., Pasal 10 ayat (2)
73 Ibid., Pasal 10 ayat (3)
154
Universitas Indonesia
Badan Wakaf Indonesia.74
Dari unsur-unsur yang ada tersebut tidak ada satu
unsurpun yang menghalangi bank syari‟ah menjadi nazir wakaf uang. Namun
untuk ditunjuk menjadi LKS PWU bank syari‟ah harus memenuhi persyaratan
khusus. Beberapa syarat bagi nazhir wakaf uang untuk membuka rekening dan
memperoleh dana wakaf uang dari LKS-PWU adalah:75
a. Menyampaikan permohonan secara tertulis kepada menteri;
b. Melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum;
c. Memiliki kantor operasional di wilayah Rebublik Indonesia;
d. Bergerak dibidang keuangan syari‟ah;
e. Memiliki fungsi menerima titipan (wadi‟ah).
Ada beberapa alasan mengapa bank syari‟ah dipilih sebagai LKS-PWU,
yaitu karena dipandang memiliki beberapa keunggulan, antara lain:76
Jaringan
kantor cabang yang tersebar di seluruh Provinsi, Kabupaten maupun Kota.
Dengan relatif luasnya jaringan kantor perbankan diharapkan akan lebih
mengefektifkan sosialisasi wakaf uang kepada masyarakat, sehingga
penggalangan dana wakaf menjadi lebih optimal dan juga membantu efektifitas
dan efisiensi penyampaian dana wakaf kepada al-mauquf alaih (penerima wakaf).
Lembaga perbankan merupakan lembaga yang memiliki pengalaman dalam
mengelola dana masyarakat dan juga berpengalaman sebagai lembaga perantara.
Dengan pengalaman tersebut, apabila bank syariah diamanatkan untuk membantu
memaksimalkan wakaf uang tentunya hal itu akan bisa terwujud. Pengalaman
jaringan informasi dan peta distribusi sebagai pengelola dana untuk disalurkan
kepada pihak tertentu, lembaga perbankan memiliki akses informasi yang cukup
dan peta distribusi yang jelas kemana dana-dana tersebut akan disalurkan. Dalam
praktek operasional selanjutnya, ketiga hal tersebut menjadi hal yang paling perlu
untuk dipertimbangkan dalam mengoptimalkan penbgelolaan dana wakaf.77
Bank
74
Ibid., Pasal 11
75 Kementerian Agama Rebublik Indonesia, Op.,Cit, hlm.53
76 Ahmad Furqon “Praktik Wakaf Uang Di Bank Syari‟ah Mandiri” Jurnal IAIN
Walisongo Semarang, 2010,
77 Mustofa Edwin & Uswatun Hasanah (ed), Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, Peluang
dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat, (Jakarta: PSTTI-IU, 2001), hlm.105-106
155
Universitas Indonesia
memiliki kredibilitas dimata masyarakat dan dikontrol dengan Undang-Undang
yang berlaku. Disamping itu bank Syariah dipantau langsung oleh Dewan
Pengawas Syari‟ah, sehingga dapat lebih menjamin tentang ke-Syari‟ahan wakaf
uang ini.
Berkaitan dengan teori yang peneliti gunakan dalam penulisan ini yaitu teori
keadilan sosial yang digagas oleh Sayed Qutub dan John Raw keadalian tidak
harus sama tanpa ada perbedaan. Keadilan yang mutlak pasti membutuhkan
perbedaan, tetapi memberi kesempatan yang merata dan luas kepada mayarakat
untuk menjalani kehidupan dan tidak keluar dari prinsip-prinsip keagamaan
(Sayed Qutub). Islam tidak menginginkan semua orang memilki jumlah kekayaan
yang sama dalam hal ekonomi. Karena hal itu sangat tidak mungkin terjadi. Tetapi
islam tidak menghalalkan segala kemewahan yang mendorong manusia hanya
tertuju pada khidupan materi (dunia), tunduk pada nafsu syahwatnya, dan
menciptakan kelas-kelas yang berbeda dalam masyarakat.78
kemudian senada
dengan konsep keadilan sosial yang digagas John Rawls, yaitu keadilan sosial
yang mementingkan distribusi kekuasaan dan kekayaan yang sama, tetapi juga
mentoleransi distribusi yang berbeda bagi yang berbakat.79
Secara teoritik, dalam Islam, tujuan diberlakukannya wakaf bisa dipastikan
adalah untuk merealisasikan keadilan sosial, minimal keadilan ekonomi,
kesehatan, dan pendidikan. Hal ini karena peran wakaf lebih dominan dibanding
zakat dan sedekah lainnya. Selain sebagai tolak ukur keimanan seorang hamba,
wakaf juga merupakan institusi distribusi kekayaan agar terjadi pemerataan
ekonomi dan juga merupakan simbol dari sistem ekonomi yang dikehendaki
Islam, yaitu hak-hak Individu diakui tetapi hak-hak sosial tetap diutamakan.
Melalui wakaf dan ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) diharapkan proses
konsentrasi kekayaan tidak terjadi, tetapi justru selalu terurai tercipta
78
http://insistnet.com/teori-keadilan-sosial-sayyid-qutb/, Teori Keadilan Sosial Sayyid
Qutb, diakses tanggal 6 juli 2014.
79 Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern I, Terjemahan oleh Robert MZL
dari Sosiological Theory Clasical Founder and Contemporery Perspectives (1981), Jakarta:
Gramedia, 1994, hlm. 154-161, Ian Adam, Ideologi Politik Mutakhir,Adam, 2004, hlm. 68, 190-
199, dan Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, 1995, hlm. 83
156
Universitas Indonesia
sirkulasi atau peredaran surplus kekayaan di kalangan semua masyarakat sebagai
tujuan utama ekonomi yang sehat.80
Dalam al-Qur‟an, disebutkan tujuan distribusi ekonomi itu antara lain
terlihat dalam al-Qur‟an Surat Adz-Dzariyat: 19
Artinya: Pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta
dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.81
Pada ayat diatas menunjukkan, filantropi82
Islam, baik yang wajib maupun
yang sunnah seperti wakaf, ditujukan untuk menangulangi kemiskinan, karena
penerima prioritasnya adalah kelompok fakir dan miskin.
Islam memandang bahwa akumulasi kekayaan seseorang dibangun di atas
keringat orang-orang miskin, karena di dunia ini tidak ada seorangpun yang kaya
yang bisa beraktifitas tanpa orang-orang yang ekonominya lemah. Dalam
kenyataannya, orang-orang miskin memang sudah diberi upah atas kerjanya,
namun, jumlah keuntungan yang didapat para majikan jauh lebih berlipat ganda
dibandingkan para buruhnya yang hanya didasarkan pada Upah Minimun Povinsi
(UMP) dan sejenisnya. Oleh karena itu, wakaf dan filantropi Islam lainnya adalah
bentuk ucapan terima kasih dan kerja sama kalangan kaya dan miskin.
Wakaf untuk keadilan sosial juga terdapat dalam Peraturan Perundangan
yang ada di Indonesia yang diambil dari ajaran Islam, yaitu Pasal 5 Undang-
Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 “Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan
manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk
memajukan kesejahteraan umum”.83
Dalam peraturan perundangan sebelumnya,
80
Ismail Raj‟i Al-Faruqi dan Lois Lamya Al-Faruqi, Atlas Budaya Islam, Menjelajah
Peradaban Gemilang, Bandung: Mizan, 1998, hlm. 179-181 dan Abdul Manan, Teori dan
Praktek Ejkonomi Islam, Terjemahan dari Islamic Economics, Theory and Practice oleh M.
Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf,199, hlm. 232
81 Al-Qur‟an dan Terjemahnya, Mjamma‟ al Khadim al Haramain asy Syarifain al Malik
Fadhli Thiba‟at al Mushhaf asy Syarif, Madinah al Munawwarah, 1411 H., hlm. 859.
82 Filantropi adalah cinta kasih terhadap sesama manusia.
83 Departemen Agama RI, UU Wakaf No. 41 2004, Jakarta: Depag RI, 2004, hal. 3, 5.
157
Universitas Indonesia
yaitu Pasal 216 Buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 2 PP. No. 28
/1977, juga disebutkan hal yang hampir sama.
Fungsi wakaf dalam UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf tersebut dapat
dipahami sebagaimana tercantum dalam penjelasannya, bahwa salah satu yang
melatarbelakangi kemunculan UU tersebut adalah realitas bahwa wakaf menjadi
pokok kekuatan ekonomi Ummat Islam.84
Fungsi wakaf untuk keadilan sosial Islam sebagai mauqûf
„alaih (peruntukan wakaf) itu diperjelas lagi peruntukanya dalam dalam Pasal 22
Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam pasal tersebut
bahwa mauqûf „alaih (peruntukan) wakaf selain sarana kegiatan ibadah, juga
pendidikan, kesehatan, bantuan untuk fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu,
beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi Ummat, dan kemajuan
kesejahteraan umum lainnya.85
Selain boleh digunakan untuk kepentingan ibadah (pembangunan masjid),
lembaga pendidikan dan para gurunya, pembangunan hotel atau pemondokan
untuk para musafir, juga kebutuhan minum, pengurusan mayat seperti pembelian
kain kafan, pembangunan dan rehabilitas jembatan, untuk para penghuni
penjara, rumah sakit, perpustakan, dan lainnya. Bahkan, berbeda dengan sedekah
lainnya, sebagian wakaf atau manfaatnya pun, seperti buku dan al-Qur‟an, boleh
didistribusikan atau dimanfaatkan oleh orang kaya yang tidak berhak menerima
zakat.86
Di Indonesia sendiri telah diuntungkan dengan banyaknya perbnkan
syari‟ah, yang tidak lain telah mengembangkan dana sosial masyarakat seperti
zakat infaq dan shadaqah, namun untuk menjadi LKS PWU memerlukan syarat-
syarat khusus. Sehingga tidak semua bank syari‟ah di indonesia menjadi LKS
84
“PP No. 28/1977 tentang Perwakafan Tanah Milik”, dalam HLM. Abdul Mannan dan M
Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama, Jakarta: Rajawali Pres, 2002,
hal. 395 “Buku III Kompilasi Hukum Islam Indonesia”, dalam Abdurrahman, Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992 hlm. 166.
85 Departemen Agama RI, Undang-Undang Wakaf.
86 Abu Bakar Ahmad bin „Umar as-Syaibani, Kitâb Ahkâm al-Auqâf, Kairo: Maktabah as-
Tsaqafah ad-Diniyyah, Tthlm., hlm.294-295, „Abd al-Jalil „Abd ar-Rahman „Asyub, Kitâb al-
Waqf, Kairo: al-Afaq al-Arabiyyah, 2000, hlm. 31.
158
Universitas Indonesia
PWU yang dapat menerima wakaf uang. Bank syari‟ah juga merupakan lembaga
yang telah berhasil menerapkan asas legalitas, yaitu dengan adanya dasar hukum
Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari‟ah. Selain itu
perbankan syari‟ah juga telah mampunyai dasar hukum untuk menjamin dana
nasabah yaitu Peraturan Pemerintah RI No. 39 tahun 2005 tentang Penjaminan
Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syari‟ah. Adanya asas legalitas
tersebut adalah bentuk perlindungan hak asasi dari nasabah perbankan syari‟ah
dalam hal ini adalah dana wakaf uang untuk kesejahteraan sosial.
Keadilan tersebut tentunya berupa pemerataan bagi semua pihak, bagi bank
pengelola mendapatkan keuntungan maksimal 10 % dari keuntungan dana wakaf
tersebut, selain itu dengan banyaknya dana yang dikelola bank, maka bank bisa
menambah karyawan baru sebagai solusi untuk mengurangi pengangguran,
kemudian bagi fakir miskin dapat menikmati fasilitas pendidikan dan kesehatan
yang di hasilkan dari pengelolaan wakaf tersebut.
Berdasarkan penjelasan di atas, dasar distribusi hasil wakaf
adalah istihsân atau alasan kemaslahatan (istishlah) yang dibenarkan oleh hadis
riwayat Abdullah bin Mas‟ud. Dalam hadis itu dijelaskan bahwa apa yang
dipandang baik oleh kaum muslimin, maka menurut Allah pun baik. Karena itu,
dalam pendistribusian hasil wakaf, seorang nâzhir wakaf bisa merujuk pada
alasan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Kemaslahatan
yang disebut oleh as-Syathibi adalah dharuriyyat (alasan mendesak), baik untuk
menjaga agama (hifzh al-dîn), nyawa (hifzh al-nafs), kebebasan berpikir (hifzh al-
„aql), reproduksi (hifzh al-nasl) dan hak-hak ekonomi (hifzh al-mâl). Menurut as-
Syathibi, kemasalahatan merupakan inti syari‟ah Islam, dalil universal. Bahkan,
menurut al-‟Iz bin „Abd as-Salam, seluruh hukum Islam sesungguhnya adalah
untuk kemaslahatan manusia. As-Syathibi pun berpendapat juga bahwa jika
terjadi perbedaan antara dalil naqli (al-Qur‟an dan hadis) dengan kemaslahatan,
maka keduanya harus dikompromikan. Jadi, batasan sejauh mana hasil
wakaf khairî boleh didistribusikan adalah sejauh kemaslahatan menghendakinya.
159 Universitas Indonesia
BAB 5
PENUTUP
5. 1 Kesimpulan
1. Peran bank syari‟ah di Indonesia adalah sebagai bank kustodi atau sebagai
bank penitipan dana wakaf. Secara teknis operasional, wakif menyetorkan
dana wakafnya ke bank Syari‟ah atas nama rekening BWI yang ada di bank
syari‟ah tersebut dan sebagai gantinya wakif akan mendapatkan sertifikat
wakaf Uang. Sertifikat wakaf uang tersebut diterbitkan oleh BWI dan
dititipkan di bank Syari‟ah. Sertifikat wakaf uang tersebut akan diberikan
kepada wakif dan diadministrasikan secara terpisah dari kekayaan bank agar
konsep wakaf
2. Akad Syari‟ah yang dapat dipergunakan Bank syari‟ah dalam mengelola dana
wakaf banyak sekali diantaranya adalah:
1. Al-Mudharabah
2. Al-Musyarakah
3. Al-Murabahah.
4. Al-Ijarah
Diantara akad-akad tersebut, akad syari‟ah yang paling baik untuk
digunakan adalah akad murabahah, karena akad ini lebih dapat menjamin
bahwa dana pokok wakaf tidak akan berkurang sedikitpun.
3. Cara Bank Syari‟ah dan LPS dalam Menjamin dana wakaf adalah sebagai
berikut:
a. Bank syari‟ah menerapkan langkah-langkah berikut ini:
1. Perlindungan Tidak Langsung
2. Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principles)
160
Universitas Indonesia
3. Batas Maksimum Pemberian Kredit (“BMPK”)
4. Kewajiban Mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi
5. Mengadakan Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank
6. Melindungi Nasabah Berdasarkan Undang-Undang
Perlindungan Konsumen
b. Cara LPS dalam Menjamin dana wakaf yang ada di bank syari‟ah adalah
sebagai berikut:
1. Merumuskan dan menetepkan kebijakakn dalam rangka turut aktif
memelihara stabilitas sistem perbankan;
2. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan
penyelesaian Bank Gagal (bank resolution) yang tidak berdampak
sistemik; dan
3. Melaksakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.
Selain itu Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan penyelesaian
dan penanganan Bank Gagal dengan kewenangan sebagai berikut:
a. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang
saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
b. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang di
selamatkan;
c. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap
kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak
ketigayangg merugikan bank; dan
d. Menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur
dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.
5.2. Saran-saran:
1. Pemerintah bersama DPR RI diharapkan dapat segera mewujudkan suatu
peraturan yang menyeluruh berupa sebuah undang-undang mengenai
praktik wakaf uang di Indonesia agar ada kepastian hukum bagi
masyarakat dan perbankan syari‟ah yang hendak mengoptimalkan adanya
wakaf uang di Indonesia.
161
Universitas Indonesia
2. Bank syari‟ah seharusnya meningkatkan sumber daya manusianya (SDM)
dalam hal memahami dan menangani wakaf uang sehingga peran bank
syari‟ah dalam mengelola wakaf uang pelaksanaanya lebih baik dan betul-
betul sesuai dengan syari‟ah.
3. Pemerintah seharusnya segera membentuk Lembaga penjamin Syari‟ah
untuk mengamankan dana wakaf, agar berapapun jumlahnya dana wakaf
yang ada dapat di jamin oleh pemerintah sehingga konsep wakaf yang
dana pokoknya tidak boleh berkurang sedikitpun itu tetap terjaga.
162
Universitas Indonesia
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
„Abd al-Jalil „Abd ar-Rahman „Asyub. Kitâb al-Waqf. Kairo: al-Afaq al-
Arabiyyah, 2000.
Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akademika
Pressindo, 1992.
Abdullah, M Ma‟ruf. Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syari‟ah di
Indonesia. Banjarmasin: Antasari press. 2006.
Abu al-Walid Ibn Rusyd. Fashl al-Maqâl fimâ Baina al- Hikmah wa as-Syarî‟ah
min al-Ittishâl. Kairo: Dar al-Ma‟arif, 1999.
Abu Bakar Ahmad bin „Umar as- Syaibani. Kitâb Ahkâm al-Auqâf. Kairo:
Maktabah as-Tsaqafah ad-Diniyyah, Tth.
Abu Zahrah, Muhammad. Muhâdarât Fî al-Waqf. Kairo: Dar al-Fikr,Tth.
Adam, Ian. Ideologi Politik Mutakhir, Konsep, Ragam, Kritik, dan Masa
Depanya. Terjemahan dari Political Ideology Today. Yogyakarta:
Qalam, 2004
Ad-Dimyathi. I‟ânah at-Thâlibin. Jilid III. Bandung: al-Ma‟arif, Tth.
Adham, Fauzi Kamal. al-Idârah a-Islâmiyyah, Dirâsah Muqâranah Baina an-
Nizhâm al-Islâmiyyah wa al-Wadh‟iyyah al-Hadîtsah. Beirut: Dar an-
Nafa‟is, 2001.
Ahmad Muhammad as-Sa‟ad dan Muhammad Ali al-‟Umri. Al-Ittijâhât Al-
Mu‟âshirah Fi Tathwîr Al-Istitsmâr Al-Waqfi. Kuwait: Al-Amanah Al‟amah
Li Al-Auqaf, 2000
Ahmad, Abu Bakar bin „Umar as-Syaibani. Kitâb Ahkâm al-Auqâf. Kairo:
Maktabah as-Tsaqafah ad-Diniyyah, Tth.
Amin, Muhammad. Ijtihad Ibn Taimiyah dalam Bidang Fiqh. Jakarta:
INIS, 1991.
Antonio, Syafi'i Muhammad. Bank Syariah Dari Teori ke Praktik. penyunting
Dadi M.H. Basri, Farida R. Dewi, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
Anwar, Syamsul. Studi Hukum Islam Kontemporer. Yogyakarta: Cakrawala,
2006.
Arifin, Johan. Fiqih Perlindungan Konsumen. Semarang: Rasali Semarang, 2007.
Arifin, Zainul. Dasar-dasar Manajemen Bank Syari‟ah, Alfabeth. Jakarta: 2002.
Asikin, Zainal. Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia. PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta: 1995.
Al-„Asqalani, Ibn Hajar. Bulûgh al-Marâm. Bandung: al-Ma‟arif, Tth.
Aziz, M. Amin. Mengembangkan Bank Islam Di Indonesia. Jakarta: Bankit, 1992.
163
Universitas Indonesia
Al-Faruqi, Ismail Raj‟i dan Lois Lamya Al-Faruqi. Atlas Budaya Islam,
Menjelajah Peradaban Gemilang. Bandung: Mizan, 1998.
Al-Hanafi, Syeikh Burhanuddin Ibrahim. Kitâb al-As‟ âf Fî Ahkâm al-
Auqâf. Kairo: Hindiyah, 1902.
Ali, Fachry, Islam Keprihatinan Universal dan Politik Indonesia. Jakarta: Pustaka
Antar Kota, 1984.
Ali, Zainuddin, Hukum Perbankan Syari‟ah. Jakarta : CV Sinar Grafika, 2008
Ali, Mukti, Islam dan Sekulerisme di Turki Modern. Jakarta: Djambatan, 1994.
Departemen Agama Rebublik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahnya. Jakarta.
2008.
Direktorat Pemberdayaan wakaf Dirjen bimas Islam; Paradigma Baru wakaf di
Indonesia. Jakarta: Departemen Agama. 2006.
Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, Fiqh Wakaf. Jakarta:
Departemen Agama. 2006.
Fuadi, Munir. Hukum Perbankan Indonesia Bandung: 1999
Furqon, Ahmad. Praktik Wakaf Uang Di Bank Syari‟ah Mandiri. Jurnal IAIN
Walisongo Semarang, 2010.
GH Garcia, Gillian (1). “Deposit Insurance: Obtaining the Benafit and Avoiding
the Pitfalls”. IMF, Wasinton DC: 1996
Hamid, Arifin. Hukum Ekonomi Islam. (Ekonomi Syari‟ah) di Indonesia Aplikasi
dan Prospektifnya, Bogor: Ghalia Indonesia. 2007.
Al-jalil „Abd „asyub ar-rahman „Abd Kitâb al-Waqf. Kairo: al-Afaq al-
Arabiyyah, 2000.
Johnson, Doyle Paul. Teori Sosiologi Klasik dan Modern I, Terjemahan oleh
Robert MZL dari Sosiological Theory Clasical Founder and Contemporery
Perspectives (1981). Jakarta: Gramedia, 1994.
Kamil, Sukron. Islam dan Demokrasi, Telaah Konseptual dan Historis. Jakarta
Gaya Media Pratama. 2002.
Karim, Adiwarman A. Bank-bank Islam: Analisis Fiqh dan keuangan. Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada. 2004.
Kuntowijoyo. Identitas Politik Umat Islam. Bandung: Mizan, 1997
Mannan, M. Abdul. Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Terjemahan dari Islamic
Economics. Theory and Practice oleh M. Nastangin, Yogyakarta: Dana
Bhakti Wakaf,1997.
_________________. dan M. Fauzan. Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang
Peradilan Agama. Jakarta: Rajawali Pres, 2002.
_________________. Sertifikat Waqf Tunai, sebuah Inovasi Instrumen Keuangan
Islam”. Depok: CIBER bekerjasama dengan PKTTI-UI, 2001.
164
Universitas Indonesia
_________________. Teori dan Praktek Ejkonomi Islam, Terjemahan
dari Islamic Economics, Theory and Practice oleh M.
Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf,1997.
Kementerian Agama. Direktorat Jenderal bimbingan Masyarakat Islam,
Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di
Indonesia, tahun 2013
Lembaga Kajian Hukum Ekonomi, Sejarah Perkembangan Metode Perbankan di
Indonesia Jakarta: 1990
Muhammad. Lembaga keuangan Umat Kontemporer. UII, Yogyakarta: 2000.
__________. Manajemen Bank Syari‟ah. edisi revisi, unit penerbit dan percetakan
(UPP) AMPYKPN, Yogyakarta: 2005
Muhammad Nadratuzzaman Hosen dan Sunarwin Kartika Setiati, Tuntutan
Praktis Menggunakan Jasa Perbankan Syari‟ah. Jakarta: 2008.
An-Nawawi, al-Raudhah. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Tth
Al-Malibari, Syaikh Zainuddin Abd Al-Aziz. Fath al-Mu‟în bi Syarh Qurrah al-
„Ain. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, Tth.
Al-Mughni, Syafiq. Sejarah Kebudayaan Islam di Turki. Jakarta: Logos, 1997.
Al-Nawawi, al-Raudhah. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Jilid IV. Tth.
Parasetyo, Hendro Ali Munhanif. dkk., Islam dan Civil Society Pandangan
Muslim Indonesia. Jakarta: Gramedia dan PPIM, 2000.
Perwataamadja A. Karnaen. Karnaen dan Antonio, Syafi‟i, Apa dan Bagaimana
Bank Islam. Yogyakarta: Dana Bahakti Wakaf, 1992.
Qahaf, Mundir. Manajemen Wakaf Produktif, cet 1, jakarta. Khalifa. 2000.
Al-Qardhawi , Yusuf. Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-
Islami. Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.
Raj‟i Ismail Al-Faruqi dan Lois Lamya Al-Faruqi. Atlas Budaya Islam,
Menjelajah Peradaban Gemilang. Bandung: Mizan, 1998, h. 179-181 dan
Sâbiq, Sayyid. Fiqh al-Sunnah. jilid III. Kairo: Dâr al-Tsaqafah al-Islâmiyyah,
dan Ibn Hajar al-„Asqalani, Bulûgh al-Marâm. Bandung: al-Ma‟arif, Tth.
As-Sa‟ad Ahmad Muhammad dan al-‟Umri, Muhammad Ali, Al-Ittijâhât Al-
Mu‟âshirah Fi Tathwîr Al-Istitsmâr Al-Waqfi. Kuwait: Al-Amanah Al‟amah
Li Al-Auqaf, 2000.
Sholahuddin M. Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam. Surakarta: UMS Pers.
2006,
Simorangkir, OP dalam Sentosa Sembiring. Hukum Perbankan. Mandar Madju,
Bandung: 2000.
Sjahdeini, Sutan Remy. Perbankan Islam dan kedudukannya dalam tatahukum
Perbankan Indonesia. Jakarta: Puastama Utama Grafiti, 1999
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta 1986
165
Universitas Indonesia
_________________. dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Satu
Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
Suhadi, Imam. Wakaf Untuk Kesejahtraan Umat. cet-1 Yogyakarta: PT. Dana
Bakti Prima Yasa. 2002
Sulaiman, Rasyid. Fiqh Islam. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1995.
Sumitro, Warkum. Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait
(Bmui & Takaful) di Indonesia, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 1996.
Suratmaputra, Ahmad Munif. Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Mashlahah-
Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam. Jakarta:
Pustaka Firdaus, 2002.
Al-Syatibi, Abu Ishaq Al-Syatibi. al-Muwâfaqât fî ushûl al-Syarî„ah. Beirut, Dâr
al-Hadîts al-Kutub al-„Ilmiyyah, vol. I, bagian 2, Tth.
Syaikh Zainuddin Abd Al-Aziz Al-Malibari. Fath al-Mu‟în bi Syarh Qurrah al-
„Ain. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, Tth.
Uman, Cholil. Agama Menjawab tentang berbagai masalah abad modern.
Surabaya: Ampel Suci Surabaya.1994.
Usman, Rachmadu. Aspek hukum perbankan syari‟ah.Jakarta: Sinar Grafika, cet.
I, 2012.
Al-Walid, Abu Ibn Rusyd. Fashl al-Maqâl fimâ Baina al- Hikmah wa as-
Syarî‟ah min al-Ittishâl. Kairo: Dar al-Ma‟arif, 1999.
Wirdyanigsih, dkk. Bank dalam Asuransi Islam di Indonesia. (Jakarta, Kencana
Prenada Media, 2007
_________________. et,al.,2005, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. Jakarta:
Kencana Prenada dan Badan Penerbit Fakultas hukum Universitas Indonesia
Zuhdi, Masjfuk. Masa‟il Fiqhiyyah. Jakarta: Toko Gunung Agung 1997.
B. Makalah/ Artikel
Perwataamadja A. Karnaen. “Bank, Asuransi dan Hukum Islam”, (Bahan Kuliah
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, semester gasal tahun ajaran
2000/2001)
Aula, Muhammad Abbas. “Pemberdayaan Umat Melalui Lembaga Wakaf”.
Anggota Dewan Pertimbangan BWI, dan Dosen Fiqh di Universitas Ibn
Khaldun Bogor.
E, Mulya Siregar. “Peran Perbankan Syari‟ah dalam Wakaf Tunai”. Makalah
disampaikan pada Seminar Sehari Wakaf Tunai Inovasi finansial Islam:
peluang dan tantangan dalam dalam mewujudkan kesejahtraan sosial,
jakarta, 10 November 2001.
ISBN 979-561-688-9. “Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Perbankan,
Peluang Bank Syari‟ah”. Media Indonesia 28 Mei 2001
166
Universitas Indonesia
Manan, Abdul. “Sistem Ekonomi Berdasarkan Syari‟ah” (Artikel dalam Suara
Udilag, Vol.3,No.IX, September 2006, Jakarta, MA-RI, 2006.
Nasution E, Musthafa, “Wakaf Tunai: Strategi untuk Mensejahterahkan dan
Melepasakan Ketergantungan Ekonomi”, Makalah Workshop Internasional
Pemberdayaan Ekonomi Ummat melalui Pengelalolaan Wakaf Produktif,
Batam: Wisma Haji Batam, 7-8 Januari 2002
Sitompul, Zulkarnaen. “Lembaga Penjamin Simpanan Substansi dan
Permasalahan” Jakarta: Books Terrace & Marulak Perdede. “Perspektif
Perlindungan Hukum Simpanan Dana Nasabah pada Bank”, Jurnal
Hukumj Bisnis Volume 11, 2000.
C. Kamus
Munawwir, A.W. Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap,
Surabaya:Pustaka Progressif, Cet.Ke-14, 1997
Adam Kuper dan Jessica Kuper, Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial, Jilid I, Jakarta
Rajawali Pers, 2000.
Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Enseclopedi Islam jilid 1, Jakarta: PT Ichatiar
Baru Van Hoeve. 1994.
D. Peraturan-Peraturan
Indonesia.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari‟ah.
________.Undang-Undang Nomor 41 tahn 2004 tentang Wakaf.
________.Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 41 tahn 2004 tentang Wakaf
Umum.
________.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004.
________.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan izin
usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank
________.Undang-undang No 38, LN. No.164 tahun 1999 tentang Pengelolaan
Zakat.
________.Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang bank umum
berdasarkan prinsip syari‟ah, SK Dir. BI No. 32/34/KEP/DIR Tahun 1999,
________. Surat keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Perkreditan
Rakyat Berdasarkan Prinsip syari‟ah SK Dir. BI No. 32/36/KEP/DIR tahun
1999.
________. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Perkreditan
Rakyat Berdasarkan Prinsip Syari‟ah, Pasal 27 huruf c.
167
Universitas Indonesia
________. Direktorat Perbankan Syari‟ah. Outlock perbankan Syari‟ah
Indonesia 2009. Direktorat Perbankan Syari‟ah, 2008.
________. Akta Pernyataan keputusan Para Pendiri BMM Nomor 121 tanggal 18
juni 2007 yang dibuat oleh Arry Supratno, SH, Notaris di Jakarta: 2007.
________. Pedoman Akuntansi Perbankan Syari‟ah Indonesia, Jakarta
Kementerian Agama. Peraturan Menteri Agama Rebublik Indonesia, Direktorat
Jenderal bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf,
Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia, tahun 2013
Mahkamah agung. Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Intruksi Presiden Nomor 1
tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
Pedoman Wakaf Tunai Mu‟amalat “Petunjuk Pelaksanaan Bitul Maal Mu‟amalat
PP No. 28/1977 tentang Perwakafan Tanah Milik”,
E. SUMBER INTERNET:
http://hukum-islam.com/2013/03/hukum-bunga-bank-dalam-islam/. Hukum
Bunga Bank dalam Islam. diakses pada tanggal 8 juni 2014. http://aljurem.wordpress.com/2012/01/31/dasar-hukum-dan-pengertian-
perbankan-syariah. Dasar Hukum dan Pengertian Perbankan Syari‟ah.
diakses pada tanggal 2 juni 2014.
http://suhairistain.blogspot.com/2011/12/pengelolaan-wakaf-uang-di-
baitulmaal.html. Pengelolaan Wakaf Uang di Baitul maal. diakses pada tanggal 21 maret 2014.
http://bimasIslamkulonprogo.blogspot.com/2013/08/pemberdayaan-umat-melalui-
lembaga-wakaf.html. Pemberdayaan Umat melalui Lembaga Wakaf.
diakses pada 15 juni 2014.
http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub_id=30, dikutip dari
Maclachan, Fiona C, Market Discipline in Bank Regulation; Panecea or
Paradox, The Independent Review VI, n Fall 2001
http://www1.lps.go.id/in/web/guest/simpanan-yang
dijamin;jsessionid=5E2FDF5C082313169E389A98FB071DAC. Simpanan
Yang dijamin Oleh Lembaga Penjamin Simpanan. diakses pada 15 juni
2014.