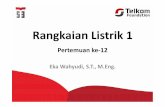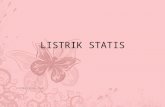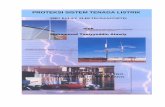Teknik Distribusi Tenaga Listrik
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Teknik Distribusi Tenaga Listrik
Teknik Distribusi TenagaListrik Suhadi
Tri Wrahatnolo
untukSekolah Menengah Kejuruan
Su
had
i | Tri Wrah
atno
lo
TE
KN
IK D
IST
RIB
US
I TE
NA
GA
LIS
TR
IK
un
tuk S
MK
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah KejuruanDirektorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan MenengahDepartemen Pendidikan Nasional
HET (Harga Eceran Tertinggi) Rp. 7.888,00
ISBN XXX-XXX-XXX-X
Buku ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah dinyatakan layak sebagai buku teks pelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2007 tanggal 5 Desember 2007 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digu-nakan dalam Proses Pembelajaran.
i
TEKNIK DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK Untuk SMK
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional
Suhadi Tri Wrahatnolo
ii
Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional Dilindungi Undang-undang
TEKNIK DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK Untuk SMK Penulis : Suhadi Tri Wrahatnolo Ilustrasi, Tata Letak : Perancang Kulit : Ukuran Buku : Diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2008
410 SUH SUHADI, Tri Wrahatnolo t Teknik Distribusi Tenaga Listrik: Untuk SMK/oleh Suhadi, Tri
Wrahatnolo. ---- Jakarta:Direktorat Pembinaan SMK. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
iii
KATA PENGANTAR Sebagai buku pegangan, presentasi dalam buku ini ditekankan pada
pokok-pokok yang diperlukan dalam praktek distribusi tenaga listrik sehari-hari. Oleh sebab itu disini akan lebih banyak terlibat gambar-gambar dan tabel-tabel dari pada rumus-rumus yang rumit. Rumus-rumus yang disajikan hanya bersifat praktis dan sederhana.
Buku ini disusun berdasar Kurikulum SMK Edisi tahun 2004, yang merupakan penyempurnaan dari Kurikulum SMK Edisi tahun 1999 sebagai bagian dari rencana jangka panjang upaya untuk lebih meningkatkan kualitas lulusan sekolah menengah kejuruan. Penulis telah berusaha maksimal untuk memenuhi harapan sesuai dengan tujuan dan misi yang ada di dalam kurikulum tersebut.
Sebagai buku panduan untuk mencapai standard kompetensi kinerja secara nasional, sangat di sadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, saran dan masukan yang konstruktif dan membangun terhadap buku ini maupun umpan balik berdasarkan pelaksanaan di lapangan sangat dinantikan dan terbuka pada semua pihak.
Penulis sangat berterima kasih kepada Sub Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyajikan karya terbaik berupa penulisan buku, walalupun masih jauh dari sempurna.
Terima kasih juga penulis sampaikan kepada bapak Munadji, BA direktur CV. Bintang Lima Surabaya, dan bapak Drs. Heru Subagyo selaku Ketua AKLI Jawa Timur dan rekan-rekan APEI yang telah memberikan referensi yang sangat bermanfaat dalam penulisan buku ini.
Akhirulkalam, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada isteri dan anak-anaknya yang telah banyak mengorbankan jam-jam istirahat, hari-hari Minggu dan hari-hari libur untuk kepentingan penulisan buku ini oleh suami dan ayah mereka.
Surabaya, Juli 2008
iv
KATA SAMBUTAN Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2008, telah melaksanakan penulisan pembelian hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui website bagi siswa SMK. Buku teks pelajaran ini telah melalui proses penilaian oleh Badan Standar Nasional Pendidikan sebagai buku teks pelajaran untuk SMK yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 tahun 2008. Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh penulis yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Departemen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para pendidik dan peserta didik SMK di seluruh Indonesia. Buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Departemen Pendidikan Nasional tersebut, dapat diunduh (download), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Dengan ditayangkannya soft copy ini akan lebih memudahkan bagi masyarakat untuk mengaksesnya sehingga peserta didik dan pendidik di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini. Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Selanjutnya, kepada para peserta didik kami ucapkan selamat belajar dan semoga dapat memanfaatkan buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.
Jakarta, Direktur Pembinaan SMK
v
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR PENULIS............................................................. PENGANTAR DIREKTUR PEMBINAAN SMK..................................... DAFTAR ISI ........................................................................................... DAFTAR GAMBAR ................................................................................ DAFTAR TABEL .................................................................................... SINOPSIS ............................................................................................ DISKRIPSI KONSEP PENULISAN .................................................... PETA KOMPETENSI ............................................................................ BAB I PENDAHULUAN ...................................................................... 1-1 Pemanfaatan Tenaga Listrik ......................................................... 1-2 Kualitas Daya Listrik .................................................................... 1-3 Keselamatan Pemanfaat Tenaga Listrik ...................................... 1-4 Sistem Ketenagalistrikan ............................................................... 1-5 Klasifikasi Sistem Tenaga Listrik ................................................. 1-6 Regulasi Sektor Ketenagalistrikan ................................................ 1-7 Standarisasi dan Sertifikasi ........................................................... BAB II SISTEM DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK .............................. 2-1 Pengertian dan Fungsi Distribusi Tenaga Listrik ....................... 2-1-1 Pengertian Distribusi Tenaga Listrik ......................................... 2-1-2 Pengelompokan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik ................... 2-2 Klasifikasi Saluran Distribusi Tenaga Listrik ............................ 2-2-1 Menurut nilai tegangannya ........................................................ 2-2-2 Menurut bentuk tegangannya .................................................... 2-2-3 Menurut jenis/tipe konduktornya ................................................. 2-2-4 Menurut susunan (konfigurasi) salurannya ................................ 2-2-5 Menurut Susunan Rangkaiannya ............................................. 2-3 Tegangan Sistem Distribusi Sekunder ......................................... 2-3-1 Sistem distribusi satu fasa dengan dua kawat .......................... 2-3-2 Sistem distribusi satu fasa dengan tiga kawat. ........................... 2-3-3 Sistem distribusi tiga fasa empat kawat tegangan 120/240 Volt 2-3-4 Sistem distribusi tiga fasa empat kawat tegangan 120/208 Volt 2-3-5 Sistem distribusi tiga fasa dengan tiga kawat ............................. 2-3-6 Sistem distribusi tiga fasa dengan empat kawat ........................ 2-3-7 Ketidaksimetrisan beban ........................................................... 2-4 Gardu Distribusi ......................................................................... 2-4-1 Gardu Beton .............................................................................. 2-4-2 Gardu metal clad (Gardu besi) .................................................. 2-4-3 Gardu Tiang Tipe Portal ........................................................... 2-4-4 Gardu Tiang Tipe Cantol ........................................................... 2-4-5 Gardu Mobil ..............................................................................
iii iv v x
xxii
xxiii
xxiv xxv
1 1 1 2 3 4 5 7
10 10 10 11 13 13 13 13 13 16 26 26 27 27 27 28 28 28 30 33 34 35 36 39
vi
2-5 Trafo Distribuis ............................................................................. 2-5-1 Trafo Buatan Indonesia ............................................................. 2-5-2 Trafo Standar "NEW JEC" ......................................................... 2-5-3 Bank Trafo .................................................................................. 2-6 Pelayanan Konsumen .................................................................. 2-6-1 Tegangan ..................................................................................... 2-6-2 Frekuensi ......................... ........................................................... 2-6-3 Kontinyuitas pelayanan .............................................................. 2-6-4 Jenis Beban ................................................................................. 2-7 Dasar-dasar Perencanaan Jaringan Distribusi ......................... 2-7-1 Kriteria Teknik Saluran Listrik ..................................................... 2-7-2 Perencanaan Konstruksi ............................................................. BAB III ALAT PEMBATAS DAN PENGUKUR ..................................... 3-1 Pembatas ....................................................................................... 3-2 Pemasangan, pengoperasian dan pemeliharaan ....................... 3-3 Alat Ukur Energi Arus Bolak-balik .............................................. 3-3-1 Prinsip-prinsip Kerja .................................................................... 3-3-2 Tang Ampere .............................................................................. 3-3-3 Register .................................................................................. 3-3-4 Transformator untuk Alat-alat Pengukuran ................................ 3-4 Jenis-jenis kWH Meter .................................................................. 3-4-1 kWh meter 1 phasa ................................................................... 3-4-2 kWh meter 3 phasa .................................................................. 3-4-3 Meter Standar ............................................................................. 3-4-4 Sistem Pengamanan kWh Meter ............................................... 3-4-5 Peneraan kWh Meter ................................................................. 3-5 Pemasangan Alat Pembatas dan Pengukur ............................... BAB IV JARINGAN DISTRIBUSI TEGANGAN RENDAH .................. 4-1 Tiang Saluran Tegangan Rendah ............................................... 4-1-1 Jenis Tiang ………………………………………………………….... 4-1-2 Menentukan/memilih Panjang Tiang …………………………....... 4-1-3 Jarak Aman Tiang Tegangan Rendah ..................................... 4-1-4 Merencanakan dan mempersiapkan mendirikan tiang ................ 4-1-5 Mendirikan/menanam Tiang ........................................................ 4-2 Saluran Tegangan Rendah .......................................................... 4-2-1 Saluran Udara Tegangan Rendah .............................................. 4-2-2 Memasang Saluran Kabel Udara Tegangan Rendah ................ 4-3 Memasang Instalasi Pembumian ............................................... 4-3-1 Definisi-Definisi Sistem Pembumian ........................................... 4-3-2 Jenis Tanah ............................................................................... 4-3-3 Tahanan Jenis Tanah ................................................................ 4-3-4 Tahanan pembumian ................................................................ 4-3-4 Tahanan pembumian ................................................................ 4-3-5 Perencanaan pemasangan peralatan ....................................... 4-4 Memasang Saluran Kabel Tanah Tegangan Rendah ...................
41 41 42 45 46 46 46 47 47 52 52 53 62 62 65 65 65 66 66 65 74 74 74 76 76 78 81 93 93 93 93 95 96 96 98 98
116 126 126 127 127 127 127 128
vii
4-4-1 Pengecekan Pekerjaan Penarikan Kabel ................................. 4-4-2 Penempatan Kabel pada Galian tanah ...................................... 4-5 Sambungan Pelayanan ............................................................... 4-5-1 Ketentuan Umum Sambungan Pelayanan .................................. 4-5-2 Konstruksi Sambungan Luar Pelayanan (SLP) ......................... 4-5-3 Penggunaan Pipa Instalasi ........................................................ 4-5-4 Konstruksi Sambungan Masuk Pelanggan (SMP) .................... 4-6 Gangguan pada Saluran Udara Tegangan Rendah .................. 4-6-1 Gangguan Hilang Pembangkit ................................................... 4-6-1 Gangguan Hilang Pembangkit ................................................... 4-6-2 Gangguan Beban Lebih .............................................................. 4-6-3 Gangguan Hubung Singkat ........................................................ 4-6-4 Gangguan Tegangan Lebih ....................................................... 4-6-5 Gangguan Instabilitas ................................................................ 4-6-6 Gangguan karena konstruksi jaringan yang kurang baik ........... 4-7 Mengatasi Gangguan pada Sistem Tenaga Listrik .................. 4-7-1 Konstruksi Jaringan Listrik yang Baik ....................................... 4-7-2 Pemasangan Sistem Proteksi yang Andal ................................ 4-8 Pengaman terhadap Tegangan Sentuh .................................... 4-8-1 Cara Pengamanan terhadap Tegangan Sentuh ....................... 4-8-2 Pentanahan Tegangan Rendah ................................................. 4-8-3 Pengaman Terhadap Arus Lebih TR ........................................ 4-8-4 Pengaman Arus Lebih TR ....................................................... 4-8-5 Menentukan Kapasitas Pengaman Lebur ................................. 4-8-6 Koordinasi Pengaman Lebur ...................................................... BAB V JARINGAN DISTRIBUSI TEGANGAN MENENGAH .............. 5-1 Konsep Dasar dan Sistem ............................................................ 5-1-1 Ruang Lingkup ........................................................................... 5-1-2 Karakteristik Perlengkapan …………………………………........ 5-1-3 Perlengkapan Hubung Bagi TR Gardu Distribusi ...................... 5-1-4 Karakteristik Jaringan Distribusi Saluran Kabel Tanah .............. 5-1-5 Karakteristik Jaringan Distribusi Saluran Udara ......................... 5-1-6 Kontinyuitas Pelayanan ............................................................ 5-1-7 Langkah-langkah Meningkatkan Kontinyuitas Pelayanan ........ 5-1-8 Aspek Proteksi pada JTM ......................................................... 5-1-9 Aspek Proteksi pada Pembangkit .............................................. 5-1-10 Aspek Pembumian pada JTM ............................................... 5-1-11 Aspek-aspek Pembumian titik netral transformator tenaga di
Gardu Induk pada .................................................................. 5-1-12 Pola jaringan TM berdasarkan aspek pembumian ................. 5-1-13 Karakteristik jaringan dengan pembumian tahanan rendah .... 5-1-14 Karakteristik jaringan dengan pembumian tahanan tinggi ...... 5-1-15 Karakteristik jaringan dengan pembumian langsung .............. 5-1-16 Karakteristik jaringan tanpa pentanahan ............................... 5-1-17 Titik pembumian pada sistem TM .........................................
141 142 158 158 160 168 168 177 177 177 177 178 179 180 180 181 181 182 182 185 187 192 194 195 199 202 202 202 203 203 203 204 206 206 207 208 208
208 208 209 209 210 210 210
viii
5-1-18 Titik-titik pembumian pada jaringan TM ................................. 5-1-19 Ketentuan-ketentuan Tentang Persyaratan Instalasi Tegangan Menengah PUIL 2000 ............................................................ 5-1-20 Susut Tegangan pada Sistem 3 fasa 3 kawat 20 kV ............... 5-1-21 Metode momen listrik Sistem 3 fasa 3 kawat 20 kV ................ 5-2 Saluran Kabel Tanah Tegangan Menengah .............................. 5-2-1 Konstruksi persilangan kabel telekomunikasi dan kabel listrik non PLN .................................................................................... 5-2-2 Persilangan kabel tanah TM dengan rel kereta api .................... 5-2-3 Persilangan dengan jalan raya atau jalan lingkungan ................ 5-2-4 Persilangan dengan saluran air dan bangunan air ..................... 5-2-5 Pendekatan kabel dengan konstruksi instalasi diatas tanah ...... 5-2-6 Prosedur Peletakan Kabel Tanah ........................................ 5-2-7 Ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat dalam PUIL ............... 5-2-8 Persiapan Pelaksanaan Penggelaran Kabel Tanah ................... 5-2-9 Menentukan jalan lintasan kabel ............................................... 5-3 Penyambungan kabel tanah ...................................................... 5-3-1 Ujung kabel sebelum penyambungan ....................................... 5-3-2 Tutup/Dop Ujung Kabel ............................................................. 5-3-3 Memberi label nama pada kabel bawah tanah .......................... 5-3-4 Pemberian tanda pada kotak sambungan (junction box)............ 5-3-5 Peralatan untuk memeriksa tegangan listrik ............................. 5-4 Saluran Udara Tegangan Menengah ......................................... 5-4-1 Prosedur Penggelaran Kabel Tegangan Menengah .................. 5-4-2 Mengidentifikasi masalah penggelaran SKTM ........................ 5-4-3 Membuat laporan ...................................................................... 5-4-4 Kotak Sambung dan Kotak Ujung Saluran Kabel Tegangan Menengah .................................................................................. 5-5 Konstruksi Saluran Udara Tegangan Menengah ..................... 5-5-1 Ketentuan-ketentuan Melaksanakan Konstruksi Saluran Udara Tegangan Menengah (sesuai PUIL 2000) ...................... 5-5-2 Hantaran dan Pemasangan Saluran Udara …………………….. 5-5-3 Kekuatan Tiang Seksi ……………………………………............ 5-5-4 Konstruksi Pemasangan Isolator ……........................................ 5-5-5 Konstruksi Elektroda Pembumian ............................................. 5-5-6 Palang Sangga (Crossarm, Travers) dengan Ukuran Tertentu . 5-5-7 Ikatan Isolator pada Hantaran .................................................... 5-5-8 Guy Wire (Trekskur) atau Kawat Penarik ................................... 5-5-9 Konstruksi Pole Top Switch ........................................................ 5-5-10 Konstruksi Arrester .................................................................. 5-5-11 Konstruksi Cut Out Fused ........................................................ 5-5-12 Konstruksi Kawat Tanah (earth wire) ....................................... 5-5-13 Konstruksi Saluran Udara Tegangan Menengah Sistem Multi Grounded 3 Fasa 4 Kawat ........................................................ 5-5-14 Konstruksi-konstruksi Setempat ...............................................
211
211 211 212 213
214 214 215 215 215 215 215 215 221 231 231 231 232 233 233 234 234 235 235
235 236
236 239 241 241 242 242 242 242 242 243 243 243
243 343 244
ix
5-5-15 Konstruksi Jaringan Tiang SUTM ............................................. 5-5-16 Konstruksi Tiang SUTM ........................................................... 5-6 Konstruksi Palang Sangga (Cross Arm, Travers) ..................... 5-7 Telekomunikasi untuk Industri Tenaga Listrik ........................... 5-7-1 Kelasifikasi ................................................................................. 5-7-2 Komunikasi dengan Kawat ....................................................... 5-7-3 Komunikasi dengan Pembawa Saluran Tenaga ......................... 5-7-4 Komunikasi Radio ...................................................................... 5-8 Baterai dan Pengisinya ................................................................ 5-8-1 Baterai ........................................................................................ 5-8-2 Pengisi ....................................................................................... BAB VI SAKELAR DAN PENGAMAN PADA JARING DISTRIBUSI 6-1 Perlengkapan Penghubung/pemisah ........................................ 6-1-1 Macam-macam PHB .................................................................. 6-1-2 Bentuk PHB ................................................................................ 6-1-3 Busbar ........................................................................................ 6-1-4 Papan Hubung Bagi Tegangan Rendah (PHB TR) ................... 6-1-5 Fungsi PHB TR ......................................................................... 6-1-6 Konstruksi PHB TR .................................................................... 6-1-7 Konstruksi PHB TR Berdiri (Standing) ...................................... 6-1-8 Pengoperasian PHB TR ............................................................. 6-1-9 Pemeliharaan PHB TR .............................................................. 6-2 Transformator ................................................................................ 6-2-1 Bagian-Bagian Dari Transformator ............................................ 6-2-2 Impedansi Trafo ........................................................................ 6-2-3 Arus Penguat ............................................................................. 6-2-4 Trafo dalam Keadaan Berbeban ................................................ 6-2-5 Pemeliharaan Gardu Trafo Tiang (GTT) .................................... 6-3 Saklar dan Fuse …..………………………………………………... 6-3-1 Load Break Switch (LBS) .......................................................... 6-3-2 Pemasangan, Pembongkaran dan Pengecekan ...................... 6-3-3 Pengujian Load Break Switch ................................................... 6-3-4 Pemasangan dan Penyambungan Surge Arrester ..................... 6-4 Pengaman .................................................................................... 6-4-1 Kepekaan (sensitivitas) ............................................................... 6-4-2 Kecermatan (Selektivitas) ........................................................... 6-4-3 Keandalan (reliability) ................................................................. 6-4-4 Kecepatan bereaksi .................................................................... 6-4-5 Pentanahan Tegangan Menengah ............................................. 6-4-6 Hubungan Sistem Pentanahan dan Pola Arus Pengaman Lebih 6-4-7 Sistem-Sistem yang Tidak Simetris ............................................ 6-4-8 Pengaman Terhadap Arus Lebih TM .......................................... 6-4-9 Hubungan Singkat Satu Kawat ke Tanah .................................. 6-5 Jenis Pengaman ............................................................................ 6-5-1 Pengaman lebur ..........................................................................
251 261 272 272 274 274 281 285 285 288 289 289 290 291 291 292 294 295 296 296 298 304 304 306 307 307 308 315 315 325 328 331 337 338 338 339 339 339 341 342 343 344 346 346
x
6-5-2 Relai Arus Lebih .......................................................................... 6-5-3 Relai Arus Gangguan Tanah ....................................................... 6-5-4 Relai Arus Gangguan Tanah Berarah ......................................... 6-5-5 Relai Penutup Balik ..................................................................... 6-5-6 Penutup Balik Otomatis ............................................................... 6-6 Saklar Seksi Otomatis ................................................................. 6-6-1 Pemilihan Pengaman Arus Lebih ................................................ 6-6-2 Pemilihan Relai Arus Lebih ........................................................ 6-6-3 Pemilihan Relai Gangguan Tanah .............................................. 6-6-4 Koordinasi Pengaman ................................................................. 6-6-5 Koordinasi Pengaman pada Jaringan Radial .............................. 6-6-6 Koordinasi Pengaman pada Jaringan Loop ................................ 6-7 Penutup Balik Otomatis (PBO) ................................................... 6-7-1 Kegagalan Pengaman ................................................................. 6-7-2 Pengaman Terhadap Tegangan Lebih ........................................ 6-7-3 Karakteristik Tegangan Surja ...................................................... 6-7-4 Pengamanan Terhadap Tegangan Lebih .................................... 6-7-5 Pengamanan Saluran Distribusi Masa Kini ................................. 6-7-6 Arrester pada Transformator Distribusi ....................................... 6-7-7 Arrester pada Recloser (PBO) ..................................................... 6-7-8 Arrester pada Kapasitor Distribusi ............................................... 6-7-9 Arrester pada Pengaman Lebur .................................................. 6-7-10 Arrester pada SUTM ................................................................ 6-7-11 Arrester pada SKTM ................................................................ 6-7-12 Kegagalan Pengamanan dan Penyebabnya ............................ 6-7-13 Pengawatan Pengaman ........................................................... DAFTAR PUSTAKA .............................................................................. DAFTAR ISTILAH .................................................................................. DATA PENULIS ............................................................................... .....
346 346 346 346 346 347 347 348 348 349 350 351 353 354 354 361 362 363 365 367 367 367 368 368 368 370 373 375 380
x
DAFTAR GAMBAR Gambar Halaman 1-1 Sistem Tenaga Listrik ................................................................... 2-1 Sistem Penyaluran Tenaga Listrik ................................................ 2-2 Pembagian/pengelompokan Tegangan Sistem Tenaga Listrik … 2-3 Konfigurasi horisontal .................................................................. 2-4 Konfigurasi Vertikal ..................................................................... 2-5 Konfigurasi Delta ......................................................................... 2-6 (a) dan (b) Jaringan distribusi lintas bangunan ............................ 2-6 (c) dan (d) Jaringan distribusi lintas bangunan ............................ 2-6(e) Jaringan distribusi lintas bangunan .......................................... 2-6 (f) Jaringan distribusi lintas bangunan ......................................... 2-7 Saluran Udara dengan konduktor kabel ...................................... 2-8 Saluran distribusi dimana saluran primer dan sekunder terletak pada
satu tiang ..................................................................................... 2-9 Saluran Udara Lintas Alam .......................................................... 2-10 Jaringan radial tipe pohon .......................................................... 2-11 Komponen Jaringan radial ......................................................... 2-12 Jaringan radial dengan tie dan switch ........................................ 2-13 Jaringan radial tipe pusat beban .............................................. 2-14 Jaringan radial tipe phase area (kelompok fasa) ………………. 2-15 Jaringan Distribusi tipe Ring ..................................................... 2-16 Jaringan Distribusi ring terbuka ................................................. 2-17 Jaringan Distribusi ring tertutup ................................................. 2-18 Rangkaian Gardu Induk tipe Ring ............................................ 2-19 Jaringan Distribusi NET ............................................................. 2-20 Jaringan Distribusi NET dengan Tiga penyulang Gardu Hubung 2-21 Jaringan Distribusi NET dilengkapi breaker pada bagian tengah
masing-masing penyulang ........................................................ 2-22 Jaringan distribusi Spindle ........................................................ 2-23 Diagram satu garis Penyulang Radial Interkoneksi .................... 2-24 Komponen sistem distribusi ....................................................... 2-25 Sistem satu fasa dua kawat tegangan 120Volt .......................... 2-26 Sistem satu fasa tiga kawat tegangan 120/240 Volt .................. 2-27 Sistem distribusi tiga fasa empat kawat tegangan 120/240 Volt 2-28 Sistem distribusi tiga fasa empat kawat tegangan 120/208 Volt 2-29 Sistem distribusi tiga fasa tiga kawat ........................................ 2-30 Sistem distribusi tiga fasa empat kawat 220/380 Volt ................. 2-31 Contoh Gambar Monogram Gardu Distribusi ............................ 2-32 Penampang Fisik Gardu Distribusi ............................................ 2-33 Bagan satu garis pelanggan TM ................................................ 2-34 Bagan satu garis Gardu Beton .................................................. 2-35 Bangunan Gardu beton ............................................................. 3-36 Bardu Besi ................................................................................. 2-37 Gardu tiang tipe portal dan Midel Panel .....................................
3 11 12 13 13 14 14 14 15 15 15
15 15 17 17 18 18 19 20 20 20 21 21 21
22 23 24 25 26 27 27 27 28 28 30 31 32 33 33 34 35
xi
2-38 Bagan satu garis Gardu tiang tipe portal .................................... 2-39 Bagan satu garis Gardu tiang tipe Cantol ................................... 2-40 Gardu tiang tiga fasa tipe Cantol ................................................ 2-41 Elektrode Pentanahan ................................................................. 2-42 Detail Pemasangan Elektrode Pentanahan ............................... 2-43 Diagram Instalasi Pembumian Gardu Distribusi ......................... 2-44 Gardu mobil ................................................................................ 2-45 Pemutus beban 20 kV tipe "Fuse Cut out" ………………………. 2-46 Trafo distribusi kelas 20 kV ………………………………………... 2-47 Hubungan dalam trafo distribusi tipe "New Jec" .......................... 2-48 Sistem satu fasa dua kawat 127 Volt ......................................... 2-49 Sistem satu fasa dua kawat 220 Volt ......................................... 2-50 Sistem satu fasa tiga kawat 127 Volt ......................................... 2-51 Sistem tiga fasa empat kawat 127/220 Volt ............................... 2-52 Sistem tiga fasa empat kawat 220/380 Volt ............................... 2-53 Bank trafo dengan ril .................................................................. 2-54 Bank trafo dilengkapi sekring sekunder pada relnya ................. 2-55 Bank trafo dengan pengamanan lengkap .................................. 2-56 Karakteristik beban untuk industri besar …………………………. 2-57 Karakteristik beban harian untuk industri kecil yang hanya bekerja pada siang hari ........................................................................... 2-58 Karakteristik beban harian untuk daerah komersiil ..................... 2-59 Karakteristik beban harian rumah tangga ................................. 2-60 Karakteristik beban penerangan jalan umum ........................... 2-61 Perbandingan nilai g untuk rumah besar dan rumah kecil .......... 2-62 Andongan .................................................................................... 2-63 Konstruksi tiang penyangga (TM-1) ............................................ 2-64 Konstruksi tiang penyangga ganda (TM-2) .................................. 2-65 Konstruksi tiang tarik akhir (TM-4) ............................................... 2-66 Konstruksi tiang tarik ganda (TM-5) ............................................. 2-67 Konstruksi tiang pencabangan (TM-8) ........................................ 2-68 Konstruksi tiang sudut (TM-10) ................................................... 2-69 Konstruksi Guy Wire ................................................................... 2-70 Konstruksi Horisontal Guy Wire .................................................. 2-71 Konstruksi Strut Pole .................................................................. 2-72 Konstruksi GTT tipe cantol ........................................................... 2-73 GTT tipe dua tiang ...................................................................... 2-74 Konstruksi Tiang Penyangga (TR-1) ........................................... 2-75 Konstruksi Tiang Sudut (TR-2) ..................................................... 2-76 Konstruksi Tiang Awal (TR-3) ..................................................... 2-77 Konstruksi Tiang Ujung (TR-3) ..................................................... 2-78 Konstruksi Tiang Penegang (TR-5) ............................................. 3-1 Miniature Circuit Breaker (MCB) .................................................... 3-2 Konstruksi KWH meter .................................................................. 3-3 Tang Ampere.................................................................................. 3-4 Bentuk-bentuk penunjukan (register) ............................................
36 37 37 38 38 39 40 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45 46 47
48 48 49 50 51 55 57 57 58 58 58 58 59 59 59 60 60 60 60 61 61 61 62 65 66 66
xii
3-5 Rangkaian Prinsip Kerja Transformator ......................................... 3-6 Transformator Arus …………......................................................... 3-7 Jenis-jenis Trafo Arus ................................................................... 3-8 Trafo Tegangan ………................................................................... 3-9 Jenis-jenis trafo tegangan ……….................................................. 3-10 Alat Pembagi Tegangan Kapasitor …........................................... 3-11 Kombinasi-kombinasi transformator pengukur dan Wattmeter .... 3-12 Pengukuran arus pada kawat penghantar ................................... 3-13 Diagram Pengawatan kWH Meter 1 phasa 2 kawat .................... 3-14 Diagram Pengawatan kWH Meter 3 phasa 4 kawat .................... 3-15 Diagram Pengawatan kWH Meter 3 phasa 3 kawat .................... 3-16 Bentuk kWH Meter Elektronik .....…………………………………. 3-17 Bentuk meter standar ................................................................. 3-18 Bentuk Kunci Elektronik ............................................................. 3-19 Sambungan Listrik 3 Fasa Tarip Ganda Dari Gardu Tiang dengan kabel TR NYFGBY ...................................................................... 3-20 Lemari APP untuk TM-TR (100 A– 500 A) (DenganTutup Luar) 3-21 Lemari APP untuk TM-TR (100 A– 500 A) (Tanpa Tutup Luar) .. 3-22 Sambungan Listrik TM Pengukuran TM Tarif Tunggal Menggu- nakan peralatan Cubicle dg Kabel TM ......................................... 3-23 Sambungan Listrik TM Pengukuran TM Tarif Ganda Mengguna- kan peralatan Cubicle dg Kabel TM kVARh (Sistem 4 kawat) ...... 3-24 Lemari Pasangan Luar untuk Penempatan Alat Ukur TT-TM ..... 3-25 Sambungan Listrik TM Pengukuran TM Tarif Tunggal Mengguna- kan Cut Out / Tiang dengan AAAC & KVARH (Sistem 3 kawat) ... 3-26 Sambungan Listrik TM Pengukuran TR Tarif Tunggal Mengguna- kan Peralatan Cubicle dengan Kabel TM & KVARH (Sistem 3 kawat/4 kawat TM) ....................................................................... 3-27 Lemari APP untuk TM-TR ( 100 A - 500 A) (dengan Tutup Luar) 3-28 Lemari APP untuk TM-TR ( 100 A - 500 A) (Tanpa Tutup Luar).. 3-29 Sambungan Listrik TM Pengukuran TR Tarif Ganda Mengguna- kan Peralatan Cubicle dengan Kabel TM & KVARH (Sistem 3 kawat/4 kawat) ............................................................................. 4-1 Konstruksi Tiang Beton ………………………………………………. 4-2 Jarak aman yang diperlukan untuk menentukan panjang tiang .... 4-3 Mendirikan tiang cara manual ....................................................... 4-4 Mendirikan Tiang dengan alat pengangkat ................................... 4-5 Kabel udara melintasi jalan umum yang dilalui kendaraan bermotor 4-6 Kabel udara yang dipasang di sepanjang jalan raya .................... 4-7 Kabel udara yang dipasang di bawah pekerjaan konstruksi ……. 4-8 Dua Kabel udara (SUTM & SUTR) dipasang pada satu tiang ..... 4-9 Kabel udara melintasi sungai ....................................................... 4-10 Kabel udara yang melintas di sebelah jembatan ........................ 4-11 Kabel udara melintasi jalur listrik saluran udara ......................... 4-12 Kabel udara yang melintasi rel kereta api ..................................
67 69 69 71 71 71 72 73 74 75 75 76 77 78
82 83 84
85
86 87
88
89 91 90
92 93 94 95 98
100 100 101 101 102 103 104 104
xiii
4-13 Kabel udara yang melalui kabel udara telekomunikasi ............. 4-14 Jarak dengan kabel telekomunikasi ........................................... 4-15 Pemasangan saluran udara di dekat kabel telekomunikasi ........ 4-16 Kabel udara yang melintasi Rel kereta api ................................. 4-17 Contoh skema jaringan tegangan rendah .................................. 4-18 Pemasangan TC pada jaringan 0o-45o pada tiang beton bulat (sudut kecil) ................................................................................. 4-19 Pemasangan TC pada jaringan 45o-120o pada tiang beton bulat
(sudut besar) .............................................................................. 4-20 Penyambungan TC pada tiang penegang tiang beton ............... 4-21 Konstruksi tiang penyangga(TR1) ............................................. 4-22 Konstruksi tiang penegang/sudut(TR2) ...................................... 4-24 Konstruksi tiang penyangga silang(TR4) .................................... 4-25 Konstruksi tiang penyangga & sudut silang (TR4A) ................ 4-26 Konstruksi tiang penyangga & sudut silang (TR4B) ................ 4-27 Konstruksi tiang penegang (TR5) .............................................. 4-28 Konstruksi tiang penegang dengan hantaran beda penampang
(TR5A) ........................................................................................ 4-29 Konstruksi tiang percabangan (TR6) .......................................... 4-30 Konstruksi tiang percabangan (TR6A) ........................................ 4-31 Konstruksi Penyambungan konduktor TC dan AAAC (TR7) ...... 4-32 Konstruksi Guy Wire (GW) ......................................................... 4-33 Konstruksi Strut Pole .................................................................. 4-34 Konstruksi Horizontal Guy Wire (GW) ........................................ 4-35 Alat pelindung dari seng ............................................................. 4-36 Kendaraan pengangkut kabel dan haspel (gulungan kabel) ...... 4-37 Kantung Perkakas Tukang Listrik (Electrician tool pouche) ....... 4-38 Kotak Perkakas (Tool box) ........................................................ 4-39 Belincong (Pick) ......................................................................... 4-40 Bor Listrik (Electric drill) .............................................................. 4-41 Cangkul (Shovel) ....................................................................... 4-42 Bor Nagel (Auger (Ginlet) ........................................................... 4-43 Bor Tangan (Hand drill) ............................................................. 4-44 Gergaji kayu (stang) ................................................................... 4-45 Gergaji kayu ............................................................................... 4-46 Kakatua ....................................................................................... 4-47 Linggis (Digging Bar) ................................................................... 4-48 Kunci Inggris ( Adjustable Wrech) ............................................... 4-49 Kikir (File) ................................................................................... 4-50 Kunci Pas (Spanner).................................................................... 4-51 Kunci Ring (Offset Wrech) .......................................................... 4-52 Pahat Beton (Concrete Chisel) .................................................. 4-53 Obeng (Screw Driver) .................................................................. 4-54 Pahat Kayu (Wood Chisel) ........................................................... 4-55 Palu (Hammer) ............................................................................ 4-56 Penjepit Sepatu Kabel Hidrolik (Hydraulic Crimping Tool) ………
105 106 107 108 108
109
109 110 110 111 111 112 112 112
113 113 113 114 114 115 115 116 116 118 118 119 119 119 119 119 119 119 119 120 120 120 120 120 120 120 120 120 121
xiv
4-57 Alat Pembengkok Pipa (Pipe Bender) ……………………………. 4-58 Sendok Aduk (Trowel) …………………………………………….. 4-59 Pisau Kupas Kabel (Line’s men knive) ………………………..... 4-60 Skop ( Spade ) ……………………………………………............. 4-61 Tang Kombinasi (Master Plier) …………………………….......... 4-62 Tang Lancip (Radio long Nose Plier) ……………………………. 4-63 Tang Pengupas Kabel (Wire Striper) …………………………..... 4-64 Tang Potong (Diagonal cutting plier) …………………………….. 4-65 Tirpit (Penarik kabel) ………………………………...................... 4-66 Ampere Meter ……………………………….................................. 4-67 Kwh Meter ………………………………...................................... 4-68 Lux Meter (Illumino Meter) ………………………………............. 4-69 Megger (Insulation Tester) ………………………………............ 4-70 Meteran Kayu/lipat (Folding wood measurer) ............................ 4-71 Meteran Pendek (Convec Rule) ................................................. 4-72 Multimeter (Multy meter) ............................................................ 4-73 Termometer (Thermometer) ....................................................... 4-74 Tespen (Electric tester) .............................................................. 4-75 Water Pas (Level) ...................................................................... 4-76 Volt meter .................................................................................... 4-77 Kacamata Pengaman (Safety goole) ……………………………… 4-78 Pelindung Kedengaran (Hearing protector) ……………………… 4-79 Pelindung Pernafasan (Dust/Mist Protector) …………………….. 4-80 Topi Pengaman (Safety Helmet/Cap) ……………………………. 4-81 Sabuk Pengaman (Safety Belt) ……………………………………. 4-82 Sarung Tangan 20 kV (20 kV Glove) ………………………........ 4-83 Sepatu Pengaman (Safety Shoe) ………………………………… 4-84 Bor Listrik Duduk (Bend Electric Drill) ……………………………. 4-85 Catok (Vise) ………………………………………………………… 4-86 Dongkrak Haspel Kabel (Cable Drum Jack) …………………..... 4-87 Disel Genset (Diesel Generator) …………………………………. 4-88 Gerinda Potong Cepat (High Speed Cutter ) ……………………. 4-89 Mesin Penarik Kabel (Winche) …………………………….......... 4-90 Molen Beton (Concrete Mixer) ……………………………........... 4-91 Pembengkok Pipa Hidrolis (Hydraulic Pipe Bender) ………...... 4-92 Pemegang Kabel (Cable Grip) .................................................... 4-93 Pompa Air (Water Pump) ............................................................ 4-94 Rol Kabel (Cable Roller .............................................................. 4-95 Tangga Geser (Extension Ladder) ............................................. 4-96 Treller Haspel Kabel (Cable Drum Trailler) ............................... 4-97 Alat Ukur Model Wenner ............................................................ 4-98 Mengukur Tahanan Tanah dengan Earth Tester Analog .......... 4-99 Pengukuran dengan Earth Resistance Tester dan Persyaratan pengukuran tahanan tanah ........................................................ 4-100 Pengukuran dengan Tang Ground Tester Digital .................... 4-101 Pemasangan Multyple Grounding ............................................
121 121 121 121 121 121 121 122 122 122 122 122 122 123 123 123 123 123 123 123 124 124 124 124 124 124 124 125 125 125 125 125 125 125125126 126 126 126 126 129 130
131 131 132
xv
4-102 Penempatan Elektrode Pengukuran ......................................... 4-103 Diagram Satu Garis PHB-TR ................................................... 4-104 Gambar Konstruksi Sistem Pembumian ................................... 4-105 Perletakan 1 kabel tanah TR tiap 1 meter di bawah berm ........ 4-106 Perletakan 2 kabel tanah TR tiap 1 meter di bawah berm ........ 4-107 Perletakan 3 kabel tanah TR tiap 1 meter di bawah berm ........ 4-108 Perletakan 4 kabel tanah TR tiap 1 meter di bawah berm ........ 4-109 Perletakan 5 kabel tanah TR tiap 1 meter di bawah berm ........ 4-110 Perletakan 6 kabel tanah TR tiap 1 meter di bawah berm ....... 4-111 Perletakan 7 kabel tanah TR tiap 1 meter di bawah berm ........ 4-112 Perletakan 8 kabel tanah TR tiap 1 meter di bawah berm ........ 4-113 Perletakan 1 kabel tanah TR tiap 1 meter di bawah berm posisi penyebrangan ................................................................. 4-114 Perletakan 1 kabel tanah TR tiap 1 meter di bawah berm posisi paralel ............................................................................. 4-115 Perletakan 1 kabel tanah TR tiap 1 meter di bawah trotoar ...... 4-116 Perletakan 2 kabel tanah TR tiap 1 meter di bawah trotoar ...... 4-117 Perletakan 3 kabel tanah TR tiap 1 eter di bawah trotoar ......... 4-118 Perletakan 4 kabel tanah TR tiap 1 meter di bawah trotoar ...... 4-119 Perletakan 5 kabel tanah TR tiap 1 meter di bawah trotoar ...... 4-120 Perletakan 6 kabel tanah TR tiap 1 meter di bawah trotoar ...... 4-121 Perletakan 7 kabel tanah TR tiap 1 meter di bawah trotoar ...... 4-122 Perletakan 8 kabel tanah TR tiap 1 meter di bawah trotoar ...... 4-123 Perletakan 1 kabel tanah TR tiap 1 meter di bawah trotoar posisi penyebrangan ................................................................. 4-124 Perletakan 1 kabel tanah TR tiap 1 meter di bawah trotoar posisi peralel .............................................................................. 4-125 Perletakan 1 kabel tanah TR tiap 1 meter melintang jalan raya aspal (digali) ............................................................................... 4-126 Perletakan 2 kabel tanah TR tiap 1 meter melintang jalan raya aspal (digali) ............................................................................... 4-127 Perletakan 3 kabel tanah TR tiap 1 meter melintang jalan raya aspal (digali) ............................................................................... 4-128 Perletakan 4 kabel tanah TR tiap 1 meter melintang jalan raya aspal (digali) .............................................................................. 4-129 Perletakan 5 kabel tanah TR tiap 1 meter melintang jalan raya aspal (digali) ............................................................................... 4-130 Perletakan 6 kabel tanah TR tiap 1 meter melintang jalan raya aspal (digali) ............................................................................... 4-131 Perletakan 7 kabel tanah TR tiap 1 meter melintang jalan raya aspal (digali) .............................................................................. 4-132 Perletakan 8 kabel tanah TR tiap 1 meter melintang jalan raya aspal (digali) ............................................................................... 4-133 Perletakan 1 kabel tanah TR tiap 1 meter melintang jalan raya aspal (digali) posisi penyebrangan .............................................
132 135 138 142 142 143 143 144 144 145 145
146
146 147 147 148 148 149 149 150 150
151
151
152
152
153
153
154
154
155
155
156
xvi
4-134 Perletakan 1 kabel tanah TR tiap 1 meter melintang jalan raya aspal (digali) posisi paralel ......................................................... 4-135 Susunan struktur penanaman kabel tanah ............................... 4-136 Pemasangan kabel tanah dengan pipa pelindung ..................... 4-137 Cara meletakkan kabel tanah di dalam tanah galian ................. 4-138 Ukuran dan penempatan untuk satu kabel dan dua kabel ......... 4-139 Ketentuan umum sambungan pelanggan .................................. 4-140 Ketentuan umum sambungan luar pelanggan ........................... 4-141 Konstruksi SLP 1 phasa jenis DX/ 3 phasa jenis QX pada STR tanpa isolasi dan berisolasi ………………………………………. 4-142 Konstruksi SLP 1 phasa jenis DX/ 3 phasa jenis QX pada STR tanpa isolasi dan STR berisolasi …………………………………. 4-143 Konstruksi SLP 1 phasa jenis DX/ 3 phasa jenis QX pada STR tanpa isolasi dan STR berisolasi ........................................ 4-144 Konstruksi SLP 1 phasa jenis DX/ 3 phasa jenis QX pada STR tanpa isolasi dan berisolasi ………………………………………. 4-145 Konstruksi SLP 1 phasa jenis DX/ 3 phasa jenis QX pada STR tanpa isolasi dan berisolasi ………………………………………. 4-146 Konstruksi SLP 1 phasa / 3 phasa jenis Twisted pada STR tanpa isolasi dan STR berisolasi ............................................. 4-147 Konstruksi SLP 1 phasa / 3 phasa jenis Twisted pada STR tanpa isolasi dan STR berisolasi ………………………………… 4-148 Konstruksi SLP 1 phasa / 3 phasa jenis Twisted pada STR tanpa isolasi dan STR berisolasi ....................................... 4-149 Konstruksi SLP 1 phasa jenis DX/ 3 phasa jenis QX padatiang atap .. ..................................................................... 4-150 Konstruksi SLP 1 phasa jenis DX/ 3 phasa jenis QX pada titik tumpu dinding/tiang kayu .................................................. 4-151 Konstruksi SLP 1 phasa jenis DX/ 3 phasa jenis QX pada titik
tumpu dinding/tiang beton ........................................................ 4-152 Konstruksi SLP 1 phasa jenis DX/ 3 phasa jenis QX pada titik tumpu dinding/tiang kayu dan beton ................................... 4-153 Konstruksi SLP 1 phasa, 3 phasa Jenis twisted pada tiang atap 4-154 Konstruksi SLP 1 phasa, 3 phasa jenis twisted pada titik tumpu
dinding/tiang kayu dan beton .................................................... 4-155 Konstruksi SLP 1 phasa, 3 phasa jenis twisted pada titik tumpu
dinding/tiang kayu ...................................................................... 4-156 Konstruksi SLP 1 phasa, 3 phasa jenis twisted pada titik tumpu
dinding/tiang kayu ...................................................................... 4-157 Konstruksi SMP dengan tiang atap untuk SR 1 phasa/3 phasa
dengan SLP jenis DX/QX dan SMP jenis NYM/NYY di luar Bangunan .................................................................................. 4-158 Konstruksi SMP dengan tiang atap untuk SR 1 phasa/3 phasa
dengan SLP jenis DX/QX dan SMP jenis NYM/NYY di luar Plapon ........................................................................................
156 157 157 157 157 158 159
160
160
161
161
162
162
163
163
164
164
165
165 166
166
166
167
167
169
xvii
4-159 Konstruksi SMP dengan titik tumpu untuk SR 1 phasa/3 phasa dengan SLP jenis DX/QX dan SMP jenis NYM/NYY di luar
Bangunan ................................................................................... 4-160 Konstruksi SMP dengan titik tumpu untuk SR 1 phasa/3 phasa
dengan SLP jenis DX/QX dan SMP jenis NYM/NYY di luar Bangunan ................................................................................... 4-161 Konstruksi SMP dengan tiang atap untuk SR 1 phasa/3 phasa tanpa sambungan jenis Twisted ................................................. 4-162 Konstruksi SMP dengan tiang atap untuk SR 1 phasa/3 phasa
tanpa sambungan jenis Twisted .............................................. 4-163 Konstruksi SMP dengan tiang atap untuk SR 1 phasa/3 phasa
tanpa sambungan jenis Twisted .............................................. 4-164 Konstruksi SMP dengan titik tumpu untuk SR 1 phasa/3 phasa
tanpa sambungan jenis Twisted .............................................. 4-165 Pemasangan APP pelanggan TR 1 phasa/3 phasa dengan OK
type I/III pada dinding yang telah ada pelindungnya ................ 4-166 Pemasangan APP pelanggan TR 1 phasa dengan OK type I
dengan pelindung tambahan ................................................... 4-167 Pemasangan APP pelanggan TR 3 phasa dengan OK type III
dengan pelindung tambahan .................................................... 4-168 Pemasangan APP pelanggan TR 3 phasa pada Gd. Trafo Tiang 4-169 Pembagian daerah pengaruh arus bolak-balik (pada 50-60 hz) terhadap orang dewasa ........................................................... 4-170 Sistem Pentanahan TR ............................................................ 4-171 Sistem Pentanahan PNP........................................................... 4-172 Kasus Putusnya Penghantar Netral pada Sistem PNP ........... 4-173 Macam-macam hubungan singkat .......................................... 4-174 Pengaman Lebur Tabung Tertutup .......................................... 4-175 Kurva leleh minimum dan kurva pemutusan maksimum dan pelebur tegangan rendah .......................................................... 4-176 Kurva leleh minimum dan kurva pemutusan maksimum dan
pelebur tegangan rendah (230/400V) Berdasarkan rekomen- dasi IEC 269 – 2 ......................................................................
4-177 Kurva leleh minimum dan kurva pemutusan maksimum dan pelebur tegangan rendah (230/400V) Berdasarkan rekomen
dasi IEC 269 – 2 ................................................................... 5-1 Pola sistem tenaga Listrik ……… ………………………........ 5-2 Pola proteksi pada saluran udara tegangan menengah … …… 5-3 Pola proteksi pada saluran kabel tanah ...................................... 5-4 Pola proteksi pada pembangkit ................................................... 5-5 Aspek Pembumian pada JTM ................................................... 5-6 Titik-titik pembumian pada jaringan ........................................... 5-7 Aturan Penanaman Kabel .......................................................... 5-8 Pekerjaaan sebelum penanaman kabel ..................................... 5-9 Peletakan Kabel Tanah ........................................................... 5-10 Pengangkutan kabel tanah tegangan menengah dengan forklif ..
169
170
171
172
172
173
173
174
175176
184 189 190 192 193 195
198
199
200 202 207 207 208 208 211 214 216 217 218
xviii
5-11 Alat pelindung dari seng .............................................................. 5-12 Saluran Kabel Tanah Tegangan Menengah ................................ 5-13 Penentuan Lintasan Kabel Tanah ................................................ 5-14 Lebar Galian dan Penanganan Kotak Sambungan ..................... 5-15 Dasar lubang galian ..................................................................... 5-16 Aturan Penamanan Kabel ............................................................ 5-17 Jembatan Kabel ........................................................................... 5-18 Konstruksi khusus penanaman kabel ......................................... 5-19 Lintasan penyebrangan kabel tanah pada gorong-gorong/parit .. 5-20 Pekerjaan penanaman kabel ….................................................. 5-21 Buis Beton ................................................................................... 5-22 Konstruksi Penanaman Kabel Tanah .......................................... 5-23 Pemasangan Kabel pada Jembatan Beton ................................. 5-24 Posisi/kedudukan kabel di dasar rak kabel ................................. 5-25 Penanganan dan Pengangkutan dengan Haspel ....................... 5-26 Alat Penarik Kabel ....................................................................... 5-27 Alat Penarik kabel (Grip) ............................................................. 5-28 Roller untuk Kabel ...................................................................... 5-29 Roll Penggelar Kabel .................................................................. 5-30 Dongkrak Kabel …........................................................................ 5-31 Penarikan kabel TM dengan Roll dibelokan normal ..................... 5-32 Penarikan kabel TM Belokan Tajam ............................................ 5-33 Penggelaran Kabel ....................................................................... 5-34 Persiapan Penyambungan Kabel ................................................ 5-35 Tutup / Dop Ujung Kabel ............................................................. 5-36 Aturan galian penyambungan ………........................................... 5-37 Penamaan Timah Label ................................................................ 5-38 Pemasangan Lebel pada Kotak Sambung ................................... 5-39 Alat Pembumian Kabel yang akan dipotong ................................ 5-40 Tutup Asbes ............................................................................... 5-41 Anyaman penghubung ................................................................. 5-42 Alat Kerja Pembumian ................................................................. 5-43 Jarak aman antara kereta api dengan tiang ................................ 5-44 Jarak aman antara SUTT dan SUTM .......................................... 5-45 Jarak aman antara Menara SUTT dan SUTM ............................. 5-46 Jarak aman antara SUTR dan SUTM .......................................... 5-47 JTM 3 fasa 20 kV Menggunakan tiang besi/beton Pin type insulator & kawat AAAC/AAAC-S per kms jarak gawang 50 meter (sistem 3 kawat) ................................................................ 5-48 JTM 3 fasa 20 kV Menggunakan tiang besi / beton Pos type
insulator & kawat AAAC/AAAC-S per kms jarak gawang 50 meter (sistem 3 kawat) ...........................................................................
5-49 JTM 3 fasa 20 kV Menggunakan tiang besi / beton dengan kabel udara Twisted 20 kV per kms jarak gawang 50 meter (sistem 3 & 4 kawat) ..................................................................................
219 219 220 220 220 221 221 222 222 223 224 224 225 226 227 227 228 228 229 229 229 230 230 231 231 232 232 233 233 234 234 234 237 238 238 239
244
245
246
xix
5-50 JTM 3 fasa 20 kV Menggunakan tiang besi / beton Pin type insulator & kawat AAAC / AAAC-S per kms jarak gawang 50 meter (sistem 4 kawat) ............................................................ 5-51 JTM 3 fasa 20 kV Menggunakan tiang besi / beton Pos type insulator & kawat AAAC/ AAAC-S per kms jarak gawang 50 meter (sistem 4 kawat) ............................................................ 5-52 JTM 1 fasa 20 kV Menggunakan tiang besi/ beton Pin type insulator & kawat AAAC / AAAC-S per kms jarak gawang 50 meter ....................................................................................... 5-53 JTM 1 fasa 20 kV Menggunakan tiang besi/beton Post type insulator & kawat AAAC / AAAC-S per kms jarak gawang 50 meter ........................................................................ 5-54 Konstruksi tiang penyangga (TM-1) ............................................ 5-55 Konstruksi tiang penyangga ganda (TM-2).................................. 5-56 Konstruksi tiang tarik akhir (TM-4) .............................................. 5-57 Detail rangkaian isolator tarik/gantung ........................................ 5-58 Konstruksi tiang penegang (TM-5) .............................................. 5-59 Konstruksi tiang penegang dengan Cut Out Switch pada tiang akhir lama (TM-4XC) .................................................................. 5-60 Konstruksi tiang tarik ganda (TM-5) ........................................... 5-61 Konstruksi penegang dengan Cut Out Switch (TM5C) .............. 5-62 Konstruksi Percabangan tiang penyangga dan tarik (TM8) ........ 5-63 Konstruksi Tiang sudut (TM10) .................................................. 5-64 Konstruksi tiang sudut dilengkapi Cut Out Switch (TM10C) …… 5-65 Konstruksi portal dua tiang (TMTP2) .......................................... 5-66 Konstruksi portal tiga tiang (TMTP3) ......................................... 5-67 Konstruksi sudut portal dua tiang (TMTP2A) .............................. 5-68 Konstruksi sudut portal tiga tiang (TMTP3A) .............................. 5-69 Konstruksi tiang akhir dengan pemasangan kabel tanah (TM11) 5-70 Konstruksi Guy Wire (GW) ......................................................... 5-71 Strut Pole (SP) ............................................................................ 5-72 Horizontal Guy Wire (HGW) ……………………………………….. 5-73 Pemasangan Cross Arm double Tumpu pada Tiang Beton Bulat 5-74 Pemasangan Cross Arm double Tumpu pada Tiang Beton H .... 5-75 Pemasangan Cross Arm Tention Support 2000 mm pada Tiang Beton Bulat .................................................................................. 5-76 Pemasangan Cross Arm Tention Support 2000 mm pada Tiang Beton H ……………………………………………………………… 5-77 Pemasangan Cross Arm Tention Support 2200 mm Double Pole pada Tiang Beton Bulat ……………………………………………. 5-78 Pemasangan Cross Arm Tention Support 2200 mm Double Pole pada Tiang Beton H ………………………………………………… 5-79 Pemasangan 2 X Tention Support 2200 mm Diatas Dua Tiang.. 5-80 Pemasangan 2 X Tention Support 2200 mm Diatas Dua Tiang Beton H ......................................................................................
247
248
249
250 251 251 252 252 253
253 254 254 255 255 256 256 257 257 258 258 259 260 260 261 262
263
264
265
266 267
268
xx
5-81 Pemasangan 2 X ½ Tention Support 2000 mm pada Tiang Beton Bulat sudut 90o ............................................................................ 5-82 Pemasangan 2 X ½ Tention Support 2000 mm pada Tiang Beton H sudut 90o ................................................................................. 5-83 Pemasangan Cross Arm 2 x T- Off pada Tiang Beton bulat ...... 5-84 Peralatan Pengait untuk komunikasi Pembawa (PLC) ............... 5-85 Peralatan Pengait (Coupling Equipment). dalam Gardu. A: Jebakan Saluran (Line Trap) B: Kapasitor Pengait (Coupling Capacitor) C: Penyaring Pengait (Coupling Filter) …… 5-86 Sistem Rangkaian Transmisi dengan Pembawa (PLC) ................ 5-87 Contoh Peralatan Radio ……………………………………………… 5-88 Contoh Sistem Komunikasi Radio Mobil untuk Pemeliharaan
Saluran ........................................................................................ 5-89 Lintasan Gelombang Mikro yang dipantulkan oleh reflektor Pasif. 5-90 Reflektor Pasif (A) dan Antena Parabola (B) Gelombang Mikro
(Panah menunjukkan Lintasan Gelombang ................................. 5-91 Penghitungan Kapasitas Baterai ................................................... 5-92 Lengkung Pelepasan Baterai ....................................................... 6-1 Bentuk lemari dengan bagian yang dapat ditarik keluar ............... 6-2 Busbar tipe terbuka (pandangan depan) ...................................... 6-3 Salah satu contoh Busbar tipe tertutup (Kubikel) ......................... 6-4 PHB/Gardu terbuka ...................................................................... 6-5 PHB TR (Out Door) ...................................................................... 6-6 Rangkaian Utama, Pengukuran & Kontrol PHB TR. ................... 6-7 PHB-TR Dua Jurusan dan Empat Jurusan ................................ 6-8 Konstruksi PHB-TR type berdiri (Standing) .................................. 6-9 Diagram Pengawatan PHB-TR .................................................... 6-10 Pemeriksaan titik sambungan dengan Thermavision .................. 6-11 Pelaksanaan Pemeliharaan Salah Satu Komponen PHB TR ...... 6-12 Diagram Segaris Gardu Trafo Tiang (GTT) ................................ 6-13 Pemasangan PHB-TR pada Gardu ............................................ 6-14 Diagram Satu Garis PHB-TR Gardu Tiang Trafo ....................... 6-15 Pemasangan PHB-TR pada Gardu Control ............................... 6-16 Rangkaian Dasar Trafo .............................................................. 6-17 Diagram Arus Penguat ............................................................... 6-18 Rangkaian Trafo Berbeban ......................................................... 6-19 Detail Load Break Switch …………………………………………. 6-20 Ruang Kontak Kontrol Load break switch ................................... 6-21 Panel Perlengkapan Load break switch ………………………….. 6-22 Menghubungkan Kabel …………………………………………….. 6-23 Melepaskan Kabel Kontrol .......................................................... 6-24 Pengujian Load Break …………………………………………….. 6-25 Terminal TeganganTinggi .......................................................... 6-26 Sambungan Suplai Tegangan Rendah ………………………….. 6-27 Sambungan Kabel Ujung …………………………………………. 6-28 Suplai Tegangan Rendah dan Terminal Grounding ……………
269
270 271 276
277 278 281
283 285
285 287 287 291 291 292 293 293 294 295 296 297 299 300 300 301 302 302 305 306 307 318 323 323 327 329 329 330 331 332 332
xxi
6-29 Gabungan Kabel supplai dari Terminal Trafo ........................... 6-30 Daerah pengamanan gangguan ............................................... 6-31 SUTM dalam keadaan gangguan satu kawat ke tanah ............ 6-32 SUTM dalam keadaan gangguan 2 kawat ke tanah .................. 6-33 SUTM dalam keadaan gangguan 3 kawat ke tanah ................. 6-34 Penempatan Rele Pengaman pada Jaringan Radial ................ 6-35 Koordinasi Pengaman pada Jaringan Radial ............................ 6-36 Koordinasi Pengaman pada Jaringan Loop .............................. 6-37 Koordinasi PBO, SSO dan FCO ................................................ 6-38 Penempatan PMT, PBO, PL dan SSO pada pangkal saluran cabang jaringan TM .................................................................... 6-39 Penempatan PMT dan PL pada jaringan Spindel SKTM (PMT tanpa PBO) Pola 2 ...................................................................... 6-40 Penempatan PMT, PBO, PL , SSO serta Saklar Tuas (ST) ....... 6-41 Penempatan PMT, SSO, ST, FCO pada SUTM ........................ 6-42 Penempatan Arester, PL dan PMT pada SUTM ........................ 6-43 Sambaran petir pada SUTM ....................................................... 6-44 Kondisi I dan II dari Jaringan Distribusi ...................................... 6-45 Muatan sepanjang tepi awan menginduksikan muatan lawan pada bumi .................................................................................. 6-46 Lidah petir menjalar ke arah bumi .............................................. 6-47 Kilat sambaran balik dari bumi ke awan ..................................... 6-48 Kumpulan muatan pada SUTM .................................................. 6-49 Gelombang tegangan uji impuls 1,2 x 50 mikro detik .................. 6-50 Skema Sambaran Petir yang Dialihkan Arrester ke Tanah ..........
6-51 Pengamanan dengan arrester tanpa interkoneksi terminal Pentanahan .................................................................................. 6-52 Pengamanan dengan arrester dan interkoneksi ke terminal
pentanahan (solid) ....................................................................... 6-53 Pengamanan dengan arrester dan interkoneksi pentanahan melalui celah (gap) ....................................................................... 6-54 Hubungan arrester pada sistem bintang yang diketanahkan 6-55 Pemakaian arrester pada sistem delta ........................................ 6-56 Hubungan arrester yang direkomen-dasikan untuk sisi beban di bagian primer pelebur (PL) ...................................................... 6-57 Tegangan pada SKTM akibat sambaran petir pada SUTM ....... 6-58 Penghantar putus sehingga arus mengalir ke tanah ................... 6-59 Kegagalan sambungan kawat pada terminal trafo ..................... 6-60 Bushing trafo pecah ................................................................... 6-61 Perangkat Relai Pengaman Arus Lebih ..................................... 6-62 Diagram satu garis pengaman JTM ............................................ 6-63 Pengawatan pengaman dengan relai OCR ............................... 6-64 Diagram pengawatan AC dengan kontrol DC dari OCR/GFR (Metoda 2 OCP) ..........................................................................
333 337 343 343 344 359 350 351 351
353
354 355 356 357 358 368
359 359 360 360 362 364
365
365
365 366 366
367 368 359 370 370 370 371 371
372
xxii
DAFTAR TABEL Tabel Halaman
2-1 Penggolongan tarif tenaga listrik ............................................... 2-2 Nilai g untuk bermacam-macam jenis beban ………….………. 2-3 Daya hantar arus AAAC & XLPE cable TR ............................... 3-1 Jenis Pembatas dan Penggunaannya …………………..……… 3-2 Contoh Data Teknik Pemutus Tenaga (MCB) .......................... 3-3 Arus Mula ................................................................................. 3-4 Batas Kesalahan Presentase yang Diijinkan ………………...... 4-1 Memilih Panjang Tiang .............................................................. 4-2 Batas minimum penggunaan tiang beton Pada jaring SUTR– TIC khusus ............................................................................... 4-3 Spesifikasi kabel LVTC ............................................................. 4-4 Tahanan Jenis Tanah ............................................................... 4-5 Nilai rata-rata Tahanan Elektrode Bumi ................................. 4-6 Ukuran galian tanah untuk beberapa pipa beton ..................... 4-7 Daftar material konstruksi SMP dengan tiang atap dan titik tumpu untuk SR 1 phasa/3 phasa dengan SLP jenis DX/QX dan
SMP jenis NYM/NYY................................................................ 4-8 Daftar material konstruksi SMP dengan tiang atap/titik tumpu
untuk SR 1 phasa/3 phasa tanpa sambungan jenis Twisted.... 4-9 Tegangan sentuh yang aman sebagai fungsi dari waktu .......... 4-10 Tahanan tubuh sebagai fungsi dari tegangan sentuh .............. 4-11 Kuat Hantar Arus Pangeman Lebur ......................................... 4-12 KHA Penghantar Tembaga A2C dan A3C ............................... 4-13 Rekomendasi pemilihan arus pengenal pelebur 24 kV jenis
letupan (Publikasi IEC 282-2 (1970). NEMA disisi primer berikut pelebur jenis pembatas arus (publikasi IEC 269-2 (1973)(230/400V) disisi sekunder yang merupakan pasangan yang diserahkan sebagai pengaman trafo distribusi.................
4-14 Persamaan kurva ketahanan untuk bermacam-macam jenis isolasi ........................................................................................ 5-1 Momen listrik kabel dan hantaran udara TM (20kV) pada beban
diujung penghantar dengan susut tegangan 5% ......................... 5-2 Pemilihan Kekuatan Tiang Ujung Jaring Distribusi Tegangan Menengah …………………………………………………………….. 5-3 Jenis-jenis Fasilitas Komunikasi ................................................ 5-4 Karakteristik dan Struktur Kabel Telekomunikasi ...................... 5-5 Contoh spesifikasi Peralatan Pembawa Saluran tenaga .......... 5-6 Contoh spesifikasi Peralatan Radio .......................................... 6-1 Material Pemeliharaan GTT ...................................................... 6-2 Tabel Daya dan Arus Fuse Link .............................................. 6-3 Tabel Daya dan Arus Fuse Link ............................................... 6-4 Kabel standar ........................................................................... 6-5 Panduan Pengujian Switchgear ...............................................
4951 54 63 63 80 81 94
95 99
127 128 157
168
171 185 185 196 197
197
201
212
240 272275 279 280 310 313 314 317 336
xxiii
SINOPSIS Buku ini menekankan pokok-pokok yang diperlukan dalam praktek
distribusi tenaga listrik sehari-hari. Pengguna buku ini adalah siswa SMK jurusan teknik distribusi tenaga listrik. Di dalam buku ini banyak disajikan gambar-gambar yang dapat membantu/mempermudah para siswa agar mengenal materi yang ada di lapangan/industri.
Materi dalam buku ini sebagian besar diambil dari bahan pelatihan yang dilakukan oleh para praktisi (kontraktor listrik), tingkat Ahli Madya (setara D3) dan Ahli Muda (setara SMK), juga materi pelatihan dari diklat yang sesuai dengan kompetensi yang diinginkan. Penggunaan buku ini didampingi modul yang disusun sesuai dengan Kurikulum SMK tahun 2004.
Buku ini menyajikan gambar-gambar rakitan (susunan) hasil kerja yang sudah jadi dan alat-alat kerja yang digunakan. Penulis mengharapkan para pembimbing praktik (guru) sudah memiliki keterampilan (skill) memadai sehingga mampu menjelaskan gambar – gambar yang ada. Materi dalam buku ini merupakan materi terapan yang sangat menarik untuk di kaji lebih dalam.
xxiv
DESKRIPSI KONSEP PENULISAN BUKU
1. Pendahuluan
Pemanfaatan Tenaga Listrik - Kualitas Daya Listrik - Keselamatan Pemanfaat Tenaga Listrik - Sistem Ketenagalistrikan - Klasifikasi Sistem Tenaga Listrik - Regulasi Sektor Ketenagalistrikan - Standarisasi dan Sertifikasi
2. Sistem Distribusi Tenaga Listrik Pengertian dan Fungsi Distribusi Tenaga Listrik - Kelasifikasi Saluran
Distribusi Tenaga Listrik - Tegangan Sistem Distribusi Sekunder - Gardu Distribusi - Trafo Distribusi - Pelayanan Konsumen - Dasar-dasar - Perencanaan Jaringan Distribusi
3. Alat Pembatas dan Pengukur Pembatas - Pemasangan, pengoperasian dan pemeliharaan - Alat Ukur
Energi Arus Bolak-balik - Jenis-jenis kWH Meter - Pemasangan Alat - Pembatas dan Pengukur
4. Jaringan Distribusi Teganagn Rendah Tiang Saluran Tegangan Rendah - Saluran Tegangan Rendah – Memasang Instalasi Pembumian - Memasang Saluran Kabel Tanah Tegangan Rendah - Sambungan Pelayanan - Gangguan pada Saluran Udara Tegangan Rendah - Mengatasi Gangguan pada Sistem Tenaga Listrik - Pengaman terhadap Tegangan Sentuh
5. Jaringan Distribusi Tegangan Menengah Konsep Dasar dan Sistem - Saluran Kabel Tanah Tegangan Menengah - Penyambungan kabel tanah - Saluran Udara Tegangan Menengah - Saluran Udara Tegangan Menengah - Konstruksi Palang Sangga (Cross Arm, Travers) - Telekomunikasi untuk Industri Tenaga Listrik - Baterai dan Pengisinya
6. Sakelar dan Pengaman Pada Jaring Distribusi Perlengkapan Penghubung/pemisah – Transformator - Saklar dan Fuse - Deteksi Kesalahan dan Fungsi Sectionalising - Pengukuran elektronis Tekanan Gas SF6 - Kontrol Elektronis - Indikasi Gangguan - Panel Kontrol Operator - Pemasangan, Pembongkaran dan Pengecekan – Pentanahan - Pengaman
xxv
PETA KOMPETENSI KODE, JUDUL, KOMPETENSI DAN SUB KOMPETENSI SESUAI STANDAR KERJA KOMPENTENSI NASIONAL
PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK KODE
KOMPETENSI JUDUL
KOMPETENSI SUB KOMPETENSI
BAB IV APP DIS.KON.001
(2).A Memasang APP Fasa Tunggal
Merencanakan dan menyiapkan pemasangan APP 1 fasaMemasang APP 1 FasaMemeriksa hasil pemasangan APP 1 fasa Membuat laporan berita acara pemasangan
DIS.KON.002 (2).A
Memasang APP Fasa tiga Pengukuran Langsung
Merencanakan dan menyiapkan pemasangan APP 3 fasa
Memasang APP 3 fasa Memeriksa hasil pemasangan APP 3 fasa Membuat laporan/berita acara pemasangan
DIS.KON.003 (2).A
Memasang APP Fasa tiga dengan transformator arus (TA) tegangan rendah (TR)
Merencanakan dan menyiapkan pemasangan APP 3 fasa dengan CT-TR
Memasang APP 3 fasa dengan CT – TR Memeriksa hasil pemasangan APP 3 fasa
dengan CT-TR Membuat laporan/berita acara pemasangan
DIS.KON.004 (2).A
Memasang Alat Pengukur Fasa Tiga Tegangan Menengah
Merencanakan dan menyiapkan pemasangan APP 3 fasa TM
Memasang APP 3 fasa TM Memeriksa hasil pemasangan APP 3 fasa TM Membuat laporan/berita acara pemasangan
DIS.KON.005 (2).A Memasang rele arus lebih untuk pembatas daya
Merencanakan dan menyiapkan pemasangan rele pembatas
Memasang Rele pembatas Memeriksa hasil pemasangan rele pembatas Membuat laporan/berita acara pemasangan
DIS.KON.006 (2).A Memasang alat bantu pengukuran
Merencanakan dan menyiapkan pemasangan alat bantu pengukuran
Memasang alat bantu pengukuran Memeriksa hasil pemasangan rele pembatas Membuat laporan/berita acara pemasangan
DIS.HAR.001(2).A
Memelihara instalasi APP pengukuran langsung
Menerapkan prosedur pemeliharaan Menyiapkan pemeliharaan Memelihara instalasi APP Memeriksa instalasi APP
xxvi
KODE KOMPETENSI
JUDUL KOMPETENSI SUB KOMPETENSI
Membuat laporan
DIS.HAR.002(2).A
Memelihara instalasi APP pengukuran tidak langsung
Menerapkan prosedur pemeliharaan Menyiapkan pemeliharaan Memelihara instalasi APP Memeriksa instalasi APP Membuat laporan
DIS.HAR.003(2).A
Mengganti Instalasi APP Pengukuran Langsung
Menerapkan prosedur pemeliharaan Menyiapkan penggantian Mengganti instalasi APP Memeriksa instalasi APP Membuat laporan
DIS.HAR.004(2).A
Mengganti Instalasi APP pengukuran tidak langsung
Menerapkan prosedur pemeliharaan Menyiapkan penggantian Mengganti instalasi APP Memeriksa instalasi APP Membuat laporan
BAB V TR DIS.KON.008
(2).A
Mendirikan/menanam tiang
Merencanakan dan mempersiapkan pendirian tiang dengan/tanpa penopangnya
Mendirikan tiang Memasang tiang penopang Mengindetifikasi masalah penanaman tiang Membuat laporan penanaman tiang
DIS.KON.009 (2) A Memasang saluran kabel udara tegangan rendah
Merencanakan dan mempersiapkan pemasangan SKUTR
Memasang perlengkapan pelengkap Memasang kawat tambat Menarik SKUTR Mengindetifikasi masalah pemasangan SKUTR Membuat laporan pemasangan SKUTR
DIS.KON.010 (2).A Memasang instalasi pembumian
Merencanakan dan mempersiapkan pemasangan instalasi pembumian
Memasang instalasi pembumian Mengukur tahanan elektroda Mengidentifikasi masalah pemasangan instalasi
pembumian Membuat laporan pemasangan instalasi
pembumian
xxvii
KODE KOMPETENSI
JUDUL KOMPETENSI SUB KOMPETENSI
DIS.KON.011 (1).A
Memasang konektor Saluran Kabel Udara Tegangan Rendah (SKUTR)
Merencanakan dan mempersiapkan pemasangan konektor
Memasang konektor sadapan SKUTR Memasangk konektor lurus Memasang sambungan SKUTR dengan SKTR Mengidentifikasi masalah masalah pemasangan
konektor Membuat laporan pemasangan konektor
DIS.KON.012 (2).A Menggelar saluran Kabel Tegangan Rendah (SKTR)
Merencanakan dan mempersiapkan penggelaran SKTR
Menggelar SKTR Menyambung SKTR Mengidentifikasi masalah penggelaran SKTR Membuat laporan
DIS.KON.013 (1).A
Memasang Peralatan Hubung Bagi Tegangan Rendah ( PHBTR)
Merencanakan dan mempersiapkan pemasangan PHB-TR
Memasang PHB-TR Mengidentifikasi masalah pemasangan PHBTR Membuat Laporan
DIS.KON.014 (2).A Memasang Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
Merencanakan dan mempersiapkan pemasangan SUTR
Memasang Perlengkapan pelengkap dan isolator
Memasang kawat tambat Menarik SUTR Mengidentifikasi masalah pemasangan SUTR Membuat laporan pemasangan SUTR
DIS.OPS.001(2).A Mengoperasikan sambungan pelanggan
Menerapkan prosedur pengoperasian Menyiapkan pengoperasian Menyiapkan dokumen pengoperasian Mengoperasikan sambungan pelanggan Menanggulangi masalah operasi Memeriksa dan membuat laporan
Menerapkan prosedur pengoperasian
DIS.OPS.002(2).A
Mengoperasikan Saluran Kabel Tegangan rendah (SKTR) atau opstyg tegangan rendah baru
Menyiapkan pengoperasian. Menyiapkan dokumen pengoperasian Mengoperasikan SKTR dan kabel opstyg baru Menanggulangi masalah operasi Memeriksa dan membuat laporan
xxviii
KODE KOMPETENSI
JUDUL KOMPETENSI SUB KOMPETENSI
DIS.OPS.003(2).A
Mengoperasikan peralatan hubung bagi tegangan rendah (PHB-TR) baru
Menerapkan prosedur pengoperasian Menyiapkan pengoperasian Menyiapkan dokumen pengoperasian Mengoperasikan PHB-TR Menanggulangi masalah operasi Memeriksa dan membuat laporan
DIS.OPS.004(2).A
Mengoperasikan Semi Automatic Change Over (SACO) pada jaringan tegangan rendah
Menerapkan prosedur pengoperasian Menyiapkan pengoperasian Mengoperasikan SACO Menanggulangi masalah operasi Memeriksa dan membuat laporan
DIS.OPS.005(2).A
Mengganti fuse pada Peralatan Hubung Bagi Tegangan Rendah (PHB TR)
Menerapkan prosedur pengoperasian Menyiapkan pengoperasian Mengganti Fuse PHB-TR Memeriksa dan membuat laporan
DIS.OPS.006(2).A Mengoperasikan saluran udara tegangan rendah
Menerapkan prosedur pengoperasian
Menyiapkan pengoperasian. Menyiapkan dokumen pengoperasian Mengoperasikan SUTR baru Menanggulangi masalah operasi Memeriksa dan membuat laporan
DIS.OPS.007(1).A Mencari gangguan pada saluran udara tegangan rendah
Menerapkan prosedur pengoperasian Menyiapkan sarana pekerjaan Mencari gangguan pada SUTR Menanggulangi masalah operasi Memeriksa dan membuat laporan
DIS.OPS.008(2).A
Mengidentifikasi gangguan pada sistem Alat Pembatas dan Pengukur (APP)
Menerapkan prosedur pengoperasian Menyiapkan pelaksanaan Menyiapkan dokumen pengoperasian Melaksanakan identifikasi sistem APP Menanggulangi masalah operasi Memeriksa dan membuat laporan
BAB VI TM DIS.KON.015
(2).A
Menggelar Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM )
Merencanakan dan mempersiapkan penggelaran SKTM
Menggelar SKTM
xxix
KODE KOMPETENSI
JUDUL KOMPETENSI SUB KOMPETENSI
Mengidentifikasi masalah penggelaran SKTM Membuat laporan
DIS.KON.016 (2).A
Memasang kotak sambung dan kotak ujung Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)
Merencanakan dan mempersiapkan pemasangan kotak sambung dan kotak ujung SKTM
Memasang kotak sambung Melakukan berbagai macam pembubutan Memasang kotak ujung Memasang arester dan instalasi pembumian Mengidentifikasi masalah pemasangan kotak
sambung dan kotak ujung Membuat laporan
DIS.KON.017 (2).A
Memasang Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM )
Merencanakan dan mempersiapkan pemasangan SUTM
Memasang perlengkapan pelengkap dan isolator Memasang kawat tambat Menarik SUTM Mengidentifikasi masalah pemasangan SUTM Membuat laporan pemasangan SUTM
DIS.KON.018 (2).A
Memasang peralatan penghubung/pemisah
Merencanakan dan mempersiapkan pemasangan SUTM
Memasang peralatan penghubung/pemisah Mengidentifikasi masalah pemasangan
peralatan penghubung/pemisah Membuat laporan
DIS.KON.019 (2).A
Memasang Saluran Kabel Udara Tegangan Menengah (SKUTM )
Merencanakan dan mempersiapkan pemasangan SKUTM
Memasang perlengkapan pelengkap Memasang kawat tambat Menarik SKUTM Mengidentifikasi masalah pemasangan SKUTM Membuat laporan
DIS.KON.020(2).A
Memasang kotak ujung dan kotak sambung Saluran Kabel Udara Tegangan Menengah (SKUTM)
Merencanakan dan mempersiapkan pemasangan kotak ujung dan kotak sambung SKUTM
Memasang Kotak sambung Memasang kotak ujung Membuat laporan
DIS.OPS.009(2).A
Mengoperasikan Saluran Kabel Tegangan
Menerapkan prosedur pengoperasian. Menyiapkan pengoperasian
xxx
KODE KOMPETENSI
JUDUL KOMPETENSI SUB KOMPETENSI
Menengah (SKTM) Baru
Menyiapkan dokumen pengoperasian Mengoperasikan jaringan SKTM Menanggulangi masalah operasi Memeriksa dan membuat laporan
DIS.OPS.010(2).A Melokalisir gangguan pada SKTM
Menerapkan prosedur pengoperasian Menyiapkan pengoperasian Menyiapkan dokumen pengoperasian Mengoperasikan jariangan SUTM Menganggulangi masalah operasi Memeriksa dan membuat laporan
DIS.OPS.011(2).A
Mengoperasikan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM ) Baru
Mengoperasikan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM ) Baru
DIS.OPS.013(2).A Mengganti fuse cut out pada SUTM
Menerapkan prosedur pengoperasian. Menyiapkan pengoperasian Melaksanakan penggantian Fuse Link Menanggulangi masalah operasi Membuat laporan penggantian Fuse
DIS.HAR.037(1).A
Memelihara instalasi Ground Fault Detector (GFD)
Menerapkan prosedur pemeliharaan Menyiapkan pemeliharaan GFD Memelihara GFD Memeriksa dan membuat laporan pemeliharaan
DIS.KON.025(1).A
Memasang Indikator Gangguan Tanah (IGT)
Merencanakan dan mempersiapkan pemasangan IGT
Memasang IGT Mengidentifikasi masalah pemasangan
peralatan penghubung/pemisah Membuat laporan pemasangan IGT
DIS.HAR. 035(2).A Memelihara sistem komunikasi suara
Menerapkan prosedur pemeliharaan Menyiapkan pemeliharaan Memelihara instalasi sistem komunikasi suara Membuat laporan pemeliharaan
DIS.HAR.039(2).A Memelihara sistem Baterai dan rectifier inverter
Menerapkan prosedur pemeliharaan Menyiapkan pemeliharaan UPS dan rectifier
catu daya Memelihara sistem UPS dan rectifier catu daya Menanggulangi masalah operasi
xxxi
KODE KOMPETENSI
JUDUL KOMPETENSI SUB KOMPETENSI
Membuat laporan pemeliharaan
BAB VII SAKLAR DAN PENGAMAN
DIS.OPS.014(2)A
Mengoperasikan Pole Top Switch (PTS)/Load Break Switch (LBS)
Menerapkan prosedur pengoperasian Menyiapkan pengoperasian Menyiapkan dokumen pengoperasian Mengoperasikan PTS dan Poletop LBS Menanggulangi masalah operasi Membuat laporan pengoperasian
DIS.OPS.015(2)A
Mengoperasikan Penutup Balik Automatic (PBO)/ Saklar Semi Automatic
Menerapkan prosedur pengoperasian Menyiapkan pengoperasian Menyiapkan dokumen pengoperasian Pengoperasian PBO dan SSO Menanggulangi masalah operasi Membuat Laporan Pengoperasian
DIS.OPS.016(2).A
Mengoperasikan Automatic Voltage Regulator (AVR) dan Cavasitor Voltage (CVR)
Menerapkan prosedur pengoperasian Menyiapkan pengoperasian Menyiapkan pengoperasian Mengoperasikan AVR dan CVR Menanggulangi masalah operasi Membuat laporan pengoperasian
Pendahuluan 1
BAB I PENDAHULUAN
1-1 Pemanfaatan Tenaga Listrik Selain memberikan manfaat, tenaga listrik mempunyai potensi
membahayakan bagi manusia dan berpotensi merusak lingkungan. Beberapa permasalahan di bidang ketenagalistrikan bila dilihat dari sisi pemanfaatan tenaga listrik banyak ditemukan instalasi tenaga listrik yang digunakan masih banyak yang belum memenuhi standar dan peralatan listrik yang beredar di masyarakat banyak yang belum memenuhi standar. Di samping itu, untuk menjamin keselamatan manusia di sekitar instalasi, keselamatan pekerja, keamanan instalansi dan kelestarian fungsi lingkungan, usaha penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik harus memenuhi ketentuan mengenai keselamatan ketenaga-listrikan.
Tenaga listrik sebagai bagian dari bentuk energi dan cabang produksi yang penting bagi negara sangat menunjang upaya dalam memajukan dan mencerdaskan bangsa. Sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, tenaga listrik perlu dipergunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sistem tenaga listrik adalah sekumpulan pusat listrik dan gardu induk (pusat beban) yang satu dengan yang lain dihubungkan oleh jaringan transmisi dan distribusi sehingga merupakan satu kesatuan yang terinterkoneksi. Suatu sistem tenaga listrik terdiri dari tiga bagian utama, yaitu: pusat pembangkit listrik, saluran transmisi, dan sistem distribusi.
Beberapa tantangan besar yang dihadapi dunia pada masa kini, antara lain, bagaimana menemukan sumber energi baru, mendapatkan sumber energi yang pada dasarnya tidak akan pernah habis untuk masa mendatang, menyediakan energi di mana saja diperlukan, dan mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk lain, serta memanfaatkannya tanpa menimbulkan pencemaran yang dapat merusak lingkungan hidup kita.
1-2 Kualitas Daya Listrik Secara umum, baik buruknya sistem penyaluran dan distribusi
tenaga listrik terutama adalah ditinjau dari kualitas daya yang diterima oleh konsumen. Kualitas Daya yang baik, antara lain meliputi: kapasitas daya yang memenuhi dan tegangan yang selalu konstan dan nominal. Tegangan harus selalu di jaga konstan, terutama rugi tegangan yang terjadi di ujung saluran. Tegangan yang tidak stabil dapat berakibat merusak alat-alat yang peka terhadap perubahan tegangan (khususnya alat-alat elektronik). Demikian juga tegangan yang terlalu rendah akan mengakibatkan alat-alat listrik tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Salah satu syarat pe-nyambungan alat-alat listrik, yaitu tegangan sumber harus sama dengan tegangan yang dibutuhkan oleh peralatan listrik tersebut. Tegangan terlalu tinggi akan dapat merusak alat-alat listrik.
Pendahuluan 2
Perubahan frekuensi akan sangat dirasakan oleh pemakai listrik yang orientasi kerjanya berkaitan/bergantung pada kestabilan frekuensi. Konsumen kelompok ini biasanya adalah industri-industri yang menggunakan mesin-mesin otomatis dengan menggunakan setting waktu/frekuensi. Kualitas daya yang baik juga harus dapat mengantisipasi timbulnya pengaruh harmonisa yang akhir-akhir ini sudah mulai menggejala. Pengaruh harmonisa disebabkan oleh adanya alat-alat elektronik, penyearah, UPS dan sebagainya.
1-3 Keselamatan Pemanfaat Tenaga Listrik Keselamatan yang berhubungan dengan ketenagalistrikan (electrical
safety) pada dasarnya adalah segala upaya atau langkah-langkah pengamanan terhadap instalasi tenaga listrik, peralatan serta pemanfaat listrik untuk mewujudkan kondisi andal dan aman, baik bagi pekerja maupun masyarakat umum.
Kita menyadari benar bahwa belum seluruh anggota masyarakat mengerti atau menyadari adanya potensi bahaya dari penggunaan listrik.
Sebagian sudah menyadari, tetapi belum mengetahui bagaimana prosedur untuk menangani pemanfaat listrik dengan benar. Untuk itu, perlu sosialisasi yang intensif untuk mencegah terjadinya bahaya dari listrik, baik terhadap jiwa manusia maupun harta benda. Resiko atas suhu yang berlebihan pada instalasi listrik adalah; (1) Bahaya api, (2) Api dapat menyebabkan hilangnya nyawa, (3) Kematian karena kejut listrik biasanya hanya menimpa pada satu orang saja.
Kematian karena kebakaran yang terjadi pada tempat dengan orang banyak, seperti tempat-tempat hiburan, pertokoan dan industri, dapat menimpa pada banyak orang pada satu kali kejadian. Penyebab timbulnya api/kebakaran pada instalasi adalah; (1) Peralatan listrik dibawah standard, (2) bencana alam, (3) manusia sebagai konsumen, (4) karena keawaman, (5) salah penggunaan, (6) kelalaian, (7) kesengajaan.
Manusia sebagai pemasang(instalatir), karena penyimpangan dari peraturan, kelalaian, dan kesengajaan. Manusia sebagai pemeriksa karena kurang teliti, kelalaian, kesengajaan, dan kegagalan pengamanan atau sistem. Untuk menangkal bahaya api listrik adalah dengan;
(1) Perlengkapan listrik dipilih yang memenuhi standard teknik (IEC Standard) dan sesuai dengan lingkungan instalasinya, agar tidak terjadi percikan api,
(2) Dimontase dengan ketentuan instalasi yang benar, atau sesuai dengan instruksi manual dari pembuatnya, kalaupun ada, dan semua sambungan dan hubungan dilakukan dengan erat,
(3) Instalasi sebaiknya diperiksa dan diuji secara periodik untuk mengetahui kemungkinan kerusakan, termasuk longgarnya sambungan/hubungan,
(4) Dengan melengkapi gawai proteksi arus sisa yang tepat, dapat menghindari kegagalan pengamanan atau sistem,
(5) Kelima, hindari kelebihan beban pada konduktor agar tidak timbul panas pada instalasi.
Pendahuluan 3
Untuk mencegah timbulnya api disarankan agar: Dilakukan penertiban mutu perlengkapan listrik yang ada dipasaran, Penyuluhan secara terus menerus lewat berbagai kesempatan, seminar, media massa, media elektronik dan sebagainya.
1-4 Sistem Ketenagalistrikan Dalam sepuluh tahun terakhir ini, masalah listrik menjadi polemik
yang berkepanjangan dan telah memunculkan multi implikasi yang sangat kompleks di berbagai aspek kehidupan, antara lain : keuangan, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lain-lain. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa listrik telah menjadi bagian yang sangat penting bagi umat manusia. Oleh karenanya tak berlebihan bahwa listrik bisa dikatakan sebagai salah satu kebutuhan utama bagi penunjang dan pemenuhan kebutuhan hidup umat manusia. Beberapa tantangan besar yang dihadapi dunia pada masa kini, antara lain, bagaimana menemukan sumber energi baru, mendapatkan sumber energi yang pada dasarnya tidak akan pernah habis untuk masa mendatang, menyediakan energi di mana saja diperlukan, dan mengubah energi dari satu ke lain bentuk, serta memanfaatkannya tanpa menimbulkan pencemaran yang dapat merusak lingkungan hidup kita. Dibanding dengan bentuk energi yang lain, listrik merupakan salah satu bentuk energi yang praktis dan sederhana. Di samping itu listrik juga mudah disalurkan dari dan
PLTA / PLTGU
GARDU INDUK STEP UP
SALURAN TRANSMISI
INDUSTRI BESAR
PERUMAHAN
PLTG
UNIT PENGATUR DISTRIBUSI
KANTOR / PERTOKOAN
SALURAN TRANSMISI
JARINGANTM / TRINDUSTRI
MENENGAH / KECIL
SEKOLAH / PERGURUAN TINGGI
PLTD
GARDU INDUK 150 kV
GARDU INDUK 70 kV
Gambar 1-1. Ruang Lingkup Sistem Tenaga Listrik
Pendahuluan 4
pada jarak yang berjauhan, mudah didistribusikan untuk area yang luas, mudah diubah ke dalam bentuk energi lain, dan bersih (ramah lingkungan). Oleh karena itu, manfaat listrik telah dirasakan oleh masyarakat, baik pada kelompok perumahan, sosial, bisnis atau perdagangan, industri dan publik. Tenaga listrik sebagai bagian dari bentuk energi dan cabang produksi yang penting bagi negara sangat menunjang upaya dalam memajukan dan mencerdaskan bangsa. Sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, tenaga listrik perlu dipergunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Yang dimaksud dengan sistem tenaga listrik adalah sekumpulan pusat listrik dan gardu induk (pusat beban) yang satu dengan yang lain dihubungkan oleh jaringan transmisi dan distribusi sehingga merupakan sebuah satu kesatuan yang terinterkoneksi. Suatu sistem tenaga listrik terdiri dari tiga bagian utama, yaitu: pusat pembangkit listrik, saluran transmisi, dan sistem distribusi. Suatu sistem distribusi menghubungkan semua beban yang terpisah satu dengan yang lain kepada saluran transmisi. Hal ini terjadi pada gardu-gardu induk (substation) di mana juga dilakukan transformasi tegangan dan fungsi-fungsi pemutusan (breaker) dan penghubung beban (switching). Gambar 1-1 memperlihatkan sistem tenaga listrik mulai dari pembangkit sampai ke pengguna/pelanggan.
1-5 Klasifikasi Sistem Tenaga Listrik Tegangan pada generator besar biasanya berkisar di antara 13,8 kV
dan 24 kV. Tetapi generator besar yang modern dibuat dengan tegangan bervariasi antara 18kV dan 24 kV. Tegangan generator dinaikkan ke tingkat yang dipakai untuk transmisi, yaitu 115 kV dan 765 kV. Tegangan tinggi standar (high voltage, HV standard) di luar negeri adalah 70 kV, 150 kV, dan 220 kV. Tegangan tinggi-ekstra standar (extra high voltage, HV standard) adalah 500 kV dan 700 kV.
Keuntungan transmisi (transmission capability) dengan tegangan lebih tinggi akan menjadi jelas jika kita melihat pada kemampuan transmisi (transmission capability) suatu saluran transmisi. Kemampuan ini biasanya dinyatakan dalam Mega-Volt-Ampere (MVA). Tetapi kemampuan transmisi dari suatu saluran dengan tegangan tertentu tidak dapat diterapkan dengan pasti, karena kemampuan ini masih tergantung lagi pada batasan-batasan termal dari penghantar, jatuh tegangan (drop voltage) yang diperbolehkan, keandalan, dan persyaratan kestabilan sistem.
Penurunan tegangan dari tingkat transmisi pertama-tama terjadi pada gardu induk bertenaga besar, di mana tegangan diturunkan ke daerah antara 70 kV dan 150 kV, sesuai dengan tegangan saluran transmisinya. Beberapa pelanggan yang memakai tenaga untuk keperluan industri sudah dapat dicatu dengan tegangan ini. Penurunan tegangan berikutnya terjadi pada gardu distribusi primer, di mana tegangan diturunkan lagi menjadi 1 sampai 30 kV. Tegangan yang lazim digunakan pada gardu-distribusi adalah 20.000 V antar-fasa atau 11.500 V antara fasa ke tanah. Tegangan ini biasanya dinyatakan sebagai 20.000 V/11.500 V. Sebagian besar beban untuk industri dicatu dengan sistem distribusi primer, yang mencatu
Pendahuluan 5
transformator distribusi. Transformator-transformator ini menyediakan tegangan sekunder pada jaringan tegangan rendah tiga-fasa empat-kawat untuk pemakaian di rumah-rumah tempat tinggal. Standar tegangan rendah yang digunakan adalah 380 V antara antar fasa dan 220V di antara masing-masing fasa dengan tanah, yang dinyatakan dengan 220/380 V.
1-6 Regulasi Sektor Ketenagalistrikan Dalam rangka meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan di sektor ketenagalistrikan, diperlukan upaya untuk secara optimal dan efisien memanfaatkan sumber energi domestik serta energi yang bersih dan ramah lingkungan, dan teknologi yang efisien guna menghasilkan nilai tambah untuk pembangkitan tenaga listrik sehingga menjamin tersedianya tenaga listrik yang diperlukan. Demikian juga dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga listrik lebih merata, adil, dan untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam hal penyediaan listrik, dapat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua pihak, baik Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Swasta untuk menyediakan tenaga listrik.
Kompetisi usaha penyediaan tenaga listrik dalam tahap awal diterapkan pada sisi pembangkitan dan di kemudian hari sesuai dengan kesiapan perangkat keras dan perangkat lunaknya akan diterapkan di sisi penjualan. Hal ini dimaksudkan agar konsumen listrik memiliki pilihan dalam menentukan pasokan tenaga listriknya yang menawarkan harga paling bersaing dengan mutu dan pelayanan lebih baik. Demikian juga kewajiban pengusaha dan masyarakat yang menggunakan tenaga listrik, juga diatur sanksi terhadap tindak pidana yang menyangkut ketenagalistrikan mengingat sifat bahaya dari tenaga listrik dan akibat yang ditimbulkannya. Di samping itu, untuk menjamin keselamatan manusia di sekitar instalasi, keselamatan pekerja, keamanan instalansi dan kelestarian fungsi lingkungan, usaha penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik harus memenuhi ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan.
Beberapa permasalahan di bidang ketenagalistrikan bila dilihat dari sisi pemanfaatan listrik juga banyak ditemukan instalasi tenaga listrik yang digunakan masih banyak yang belum memenuhi standar dan peralatan listrik yang beredar di masyarakat banyak yang sub-standar. Di sisi lainnya, perancangan, pembangunan, pemasangan, pengujian, pengoperasian dan pemeliharaan instalasi tenaga listrik dilakukan oleh tenaga teknik yang belum bersertifikat. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan menyangkut sektor ketenagalistrikan (restrukturisasi) seharusnya menjadi perhatian dan memperoleh dukungan semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.
Agar sektor ketenagalistrikan dapat menyediakan tenaga listrik yang andal, aman, memperhatikan lingkungan, efisien dan tetap menjaga nilai aset milik negara, maka dilakukan regulasi. Kerangka Regulasi meliputi; 1) aspek keteknikan, 2) peraturan keselamatan ketenagalistrikan, 3) persiapan penataan struktural, 4) persiapan pemenuhan standar lingkungan, 5) standar teknis untuk keandalan dan efisiensi sistem, 6) aturan operasi sistem, dan
Pendahuluan 6
7) program nasional. Regulasi aspek keteknikan, pertama pada sisi instalasi tenaga listrik meliputi; 1) semua fasilitas yang dipergunakan untuk pembangkitan, transmisi, distribusi dan pemanfaat tenaga listrik, 2) rancangan, konstruksi, pengujian, pemeliharaan, pengoperasian, repower instalasi tenaga listrik atau bagian-bagianya harus mengacu standar dan peraturan, Kedua, dari sisi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik, meliputi: 1) Peralatan listrik yang dijual dan instalasi tenaga listrik yang dibangun pada atau setelah tahun 2005 harus memenuhi spesifikasi teknik, standar kinerja dan keselamatan, 2) Setelah tahun 2010 (termasuk yang dibangun sebelum tahun 2005) wajib memenuhi standar, dan 3) Peralatan pemakai tenaga listrik yang terhubung ke jaringan wajib memenuhi persyaratan untuk menjaga faktor daya.
Persyaratan Umum Instalasi Listrik harus mengacu pada PUIL-2000, sebagai acuan dalam perancangan, pemasangan, pengamanan dan pemeliharaan instalasi di dalam bangunan. Peraturan Instalasi Ketenagalistrikan untuk perancangan instalasi mengacu SNI, IEC, PUIL atau Standar lain berdasarkan “the best engineering practies” dan dilakukan oleh Perusahaan Jasa Perancangan Teknik yang telah disertifikasi. Peraturan Instalasi ketenagalistrikan untuk bidang konstruksi, dilaksanakan oleh perusahaan jasa konstruksi bidang ketenagalistrikan yang telah di sertifikasi. Hasil konstruksi/pemasangan perlu diinspeksi oleh inspektur (perorangan) atau perusahaan jasa inspeksi teknik. Testing atau pengujian dilakukan untuk memastikan dan menjamin instalasi tenaga listrik telah memenuhi standar keselamatan dan standar unjuk kerja. Testing ini dilakukan oleh lembaga/perusahaan jasa inspeksi teknik yang telah diakreditasi.
Operasi dan Pemeliharaan Instalasi, merupakan tanggung jawab setiap pemilik dan perusahaan O & M, dan dilakukan oleh tenaga teknik yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang ada, diinspeksi secara berkala sesuai dengan persyaratan pelaporan operasi dan pemeliharaan.
Pelarangan memproduksi, mengimpor atau mengedarkan peralatan/pemanfaat listrik yang tidak memiliki “label keselamatan dan/atau label efisien”. Penerapan sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggaran. Peraturan Tenaga Teknik Sektor Ketenagalistrikan. Tujuan sertifikasi tenaga teknik :
a. Klasifikasi tenaga teknik sesuai kualifikasi. b. Memastikan pekerjaan dilaksanakan oleh tenaga teknik yang kompeten. c. Memastikan tenaga teknik yang bekerja di dalam negeri bersertifikasi. d. Menjamin tersediannya tenaga teknik memahami tentang keandalan,
keselamatan dan lindungan lingkungan. e. Tenaga Teknik untuk Usaha Penunjang Tenaga Listrik. f. Kualifikasinya ditentukan menurut standar kompetensi. g. Sertifikasi dilakukan oleh Organisasi Profesi yang berakreditasi.
Organisasi Profesi Tenaga Teknik dibentuk untuk membantu membuat atau menetapkan, mengimplementasikan dan mengevaluasi program akreditasi dan sertifikasi personil atau pengembangan kurikulum
Pendahuluan 7
dan program pendidikan dan pelatihan. Jasa Pendidikan dan Pelatihan mencakup usaha menciptakan sumber daya manusia yang berkualifikasi, menyiapkan SDM agar lulus sertifikasi, yang dilakukan oleh lembaga diklat yang terakreditasi.
1-7 Standarisasi dan Sertifikasi Liberalisasi perdagangan telah mengubah tatanan dunia kerja
menjadi baru. Dunia kerja yang baru tidak lagi dibatasi oleh pagar-pagar geografis atau ideologi bahkan telah tercipta suatu keadaan di mana barang dan jasa sejenis akan mengacu pada suatu standar yang secara umum sama tetapi mempunyai kekhususan tertentu dari setiap produsen. Daya saing suatu bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya dan sangat erat kaitannya dengan kompetensi kerja. Sertifikasi kompetensi membuka peluang lebih besar bagi pekerja untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kompetensinya dan menjadi kompetitif baik di pasar tenaga kerja dalam maupun luar negeri.
Tujuan sertifikasi kompetensi adalah untuk memberi kerangka pembangunan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang harmonis dan digunakan sebagai acuan bagi seluruh sektor, untuk menghasilkan tenaga kerja Indonesia yang kompeten, profesional dan kompetitif. Terciptanya sistem standarisasi dan sertifikasi kompetensi kerja nasional yang efisien dan efektif diharapkan dapat menghasilkan: a. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang bermutu
serta selaras dengan Standar Internasional untuk kebutuhan jaminan mutu internal dan kesepakatan perdagangan dalam usaha manufaktur maupun jasa.
b. Sistem penerapan standar yang dapat menunjang peningkatan efisiensi dan produktivitas.
c. Keunggulan kompetitif tenaga kerja Indonesia di pasar global d. Informasi standarisasi kompetensi yang diperlukan oleh pelaku usaha,
pemerintah dan konsumen dalam rangka meningkatkan daya saing perdagangan domestik maupun internasional.
Undang-undang No. 15 Tahun 1985, pasal 15, ayat (1) menyatakan bahwa pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan dan pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum wajib: (1) menyediakan tenaga listrik, (2) memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, dan (3) memperhatikan keselamatan kerja dan keselamatan umum. Pada pasal 17 disebutkan bahwa syarat-syarat penyediaan, pengusahaan, pemanfaatan instalasi, dan standarisasi ketenagalistrikan diatur oleh Pemerintah. Tugas Pemerintah seperti disebutkan dalam pasal 18 antara lain, (1) melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap pekerjaan dan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan, dan (2) pembinaan dan pengawasan umum tersebut meliputi keselamatan kerja, keselamatan umum, pengembangan usaha, dan terciptanya standarisasi dalam bidang ketenagalistrikan.
Pendahuluan 8
Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 tahun 2005 sebagai perubahan PP No. 10 Tahun 1989 tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik, khususnya pada pasal 21 disebutkan bahwa:
(a) Setiap usaha penyediaan tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan,
(b) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan meliputi standarisasi, pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik,
(c) Pekerjaan instalasi ketenagalistrikan untuk penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik harus dikerjakan oleh Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang disertifikasi oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi,
(d) Dalam hal di suatu daerah belum terdapat Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang telah disertifikasi, Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat menunjuk Bada Usaha Penunjang Tenaga Listrik.
Sedangkan terkait dengan pemeriksaan instalasi, pada pasal 21 disebut-kan bahwa,
(a) Pemeriksaan dan pengujian instalasi penyediaan dan instalasi pemanfaatan tegangan tinggi (TT) dan tegangan menengah (TM) dilaksanakan oleh lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi,
(b) Pemeriksaan instalasi pemanfaatan tegangan rendah (TR) oleh lembaga inspeksi independen yang sifat usahanya nirlaba,
(c) Pemeriksaan instalasi TR yang dimiliki oleh konsumen TT dan atau TM dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik yang diakreditasi, dan
(d) Setiap lembaga teknik yang bekerja dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi.
Lingkup regulasi teknik mencakup dua aspek yaitu aspek insfrastruktur teknologi dan aspek keselamatan. Aspek infrastruktur teknologi mengatur antara lain;
(a) persyaratan akreditasi dan sertifikasi, (b) standardisasi sistem, instalasi, peralatan, lengkapan dan pemanfaat
listrik serta lingkungan dan tenaga teknik, (c) peningkatan komponen dalam negeri, (d) peningkatan kualitas dan kuantitas, (e) percepatan alih teknologi.
Sedangkan aspek keselamatan mengatur antara lain, (a) penetapan standar dan pemberlakuannya, (b) kelaikan instalasi tenaga listrik, (c) kelaikan peralatan dan pemanfaatan listrik, (d) kompetensi tenaga listrik, dan (e) perlindungan lingkungan.
Acuan yang melandasi regulasi keteknikan sektor ketenagalistrikan antara lain peraturan perundang-undangan, standar peralatan dan pemanfaat tenaga listrik, standar kompetensi, baku mutu lingkungan,
Pendahuluan 9
Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2000, inspeksi ketenagalistrikan dan sanksi-sanksi.
Pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi sebagai suatu kebutuhan yang harus segera dipenuhi dalam mengikuti kemajuan teknologi yang semakin pesat. Tuntutan atas spesialisasi pekerjaan, dan persaingan global yang makin tajam yang memerlukan ketangguhan perusahaan dan kompetensi profesi. Dengan globalisasi yang bercirikan keterbukaan dan persaingan, membawa akibat suatu ancaman dan sekaligus peluang bagi tenaga kerja di semua negara. Bagaimana mewujudkan tenaga kerja yang kompeten harus melalui proses sertifikasi profesi berdasarkan standar kompetensi yang berlaku secara internasional. Implikasinya lembaga penyedia tenaga kerja baik sekolah, politeknik, akademi, perguruan tinggi, maupun lembaga pendidikan dan latihan dituntut menyelenggarakan pendidikan profesi berbasis kompetensi.
Peraturan yang telah diberlakukan mengenai standarisasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan adalah Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 2052.K/40/MEM/ 2001 tanggal 28 Agustus 2001 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, meliputi; (1) Perumusan Standar Kompetensi, (2) Akreditasi dan Sertifikasi Kompetensi, (3) Pembinaan dan Pengawasan, (4) Sanksi Administrasi, dan (5) Ketentuan Peralihan.
Tujuan standardisasi kompetensi tenaga teknik adalah untuk: (a) Menunjang usaha ketenagalistrikan dalam mewujudkan penyediaan
tenaga listrik yang aman, andal dan akrab lingkungan, (b) Mewujudkan peningkatan kompetensi tenaga teknik, dan (c) Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan pada usaha ketenaga-
listrikan.
Sistem Distribusi Tenaga Listrik
10
BAB II SISTEM DISTRIBUSI
TENAGA LISTRIK 2-1 Pengertian dan Fungsi Distribusi Tenaga Listrik 2-1-1 Pengertian Distribusi Tenaga Listrik
Sistem Distribusi merupakan bagian dari sistem tenaga listrik. Sistem distribusi ini berguna untuk menyalurkan tenaga listrik dari sumber daya listrik besar (Bulk Power Source) sampai ke konsumen. Jadi fungsi distribusi tenaga listrik adalah; 1) pembagian atau penyaluran tenaga listrik ke beberapa tempat (pelanggan), dan 2) merupakan sub sistem tenaga listrik yang langsung berhubungan dengan pelanggan, karena catu daya pada pusat-pusat beban (pelanggan) dilayani langsung melalui jaringandistribusi. Tenaga listrik yang dihasilkan oleh pembangkit tenaga listrik besar dengan tegangan dari 11 kV sampai 24 kV dinaikan tegangannya oleh gardu induk dengan transformator penaik tegangan menjadi 70 kV ,154kV, 220kV atau 500kV kemudian disalurkan melalui saluran transmisi.
Tujuan menaikkan tegangan ialah untuk memperkecil kerugian daya listrik pada saluran transmisi, dimana dalam hal ini kerugian daya adalah sebanding dengan kuadrat arus yang mengalir (I2.R). Dengan daya yang sama bila nilai tegangannya diperbesar, maka arus yang mengalir semakin kecil sehingga kerugian daya juga akan kecil pula. Dari saluran transmisi, tegangan diturunkan lagi menjadi 20 kV dengan transformator penurun tegangan pada gardu induk distribusi, kemudian dengan sistem tegangan tersebut penyaluran tenaga listrik dilakukan oleh saluran distribusi primer. Dari saluran distribusi primer inilah gardu-gardu distribusi mengambil tegangan untuk diturunkan tegangannya dengan trafo distribusi menjadi sistem tegangan rendah, yaitu 220/380Vol t . Se lan ju tnya disalurkan oleh saluran distribusi sekunder ke konsumen-konsumen. Dengan ini jelas bahwa sistem distribusi merupakan bagian yang penting dalam sistem tenaga listrik secara keseluruhan.
Pada sistem penyaluran daya jarak jauh, selalu digunakan tegangan setinggi mungkin, dengan menggunakan trafo-trafo step-up. Nilai tegangan yang sangat tinggi ini (HV,UHV,EHV) menimbulkan beberapa konsekuensi antara lain: berbahaya bagi lingkungan dan mahalnya harga perlengkapan- perlengkapannya, selain menjadi tidak cocok dengan nilai tegangan yang dibutuhkan pada sisi beban. Maka, pada daerah-daerah pusat beban tegangan saluran yang tinggi ini diturunkan kembali dengan menggunakan trafo-trafo step-down. Akibatnya, bila ditinjau nilai tegangannya, maka mulai dari titik sumber hingga di titik beban, terdapat bagian-bagian saluran yang memiliki nilai tegangan berbeda-beda.
Sistem Distribusi Tenaga Listrik
11
2-1-2 Pengelompokan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik
Untuk kemudahan dan penyederhanaan, lalu diadakan pembagian serta pembatasan-pembatasan seperti pada Gambar 3-2:
Daerah I : Bagian pembangkitan (Generation) Daerah II : Bagian penyaluran (Transmission) , bertegangan tinggi
(HV,UHV,EHV) Daerah III : Bagian Distribusi Primer, bertegangan menengah (6 atau
20kV). Daerah IV : (Di dalam bangunan pada beban/konsumen), Instalasi,
bertegangan rendah Berdasarkan pembatasan-pembatasan tersebut, maka diketahui
bahwa porsi materi Sistem Distribusi adalah Daerah III dan IV, yang pada dasarnya dapat dikelasifikasikan menurut beberapa cara, bergantung dari segi apa kelasifikasi itu dibuat. Dengan demikian ruang lingkup Jaringan Distribusi adalah:
a. SUTM, terdiri dari : Tiang dan peralatan kelengkapannya, konduktor dan peralatan per-lengkapannya, serta peralatan pengaman dan pemutus.
b. SKTM, terdiri dari : Kabel tanah, indoor dan outdoor termination, batu bata, pasir dan lain-lain.
Gambar 2-1. Sistem Penyaluran Tenaga Listrik
Sistem Distribusi Tenaga Listrik
12
c. Gardu trafo, terdiri dari : Transformator, tiang, pondasi tiang, rangka tempat trafo, LV panel, pipa-pipa pelindung, Arrester, kabel-kabel, transformer band, peralatan grounding, dan lain-lain.
d. SUTR dan SKTR terdiri dari: sama dengan perlengkapan/ material pada SUTM dan SKTM. Yang membedakan hanya dimensinya.
Gambar 2-2. Pembagian/pengelompokan Tegangan Sistem Tenaga Listrik
Sistem Distribusi Tenaga Listrik
13
2-2. Klasifikasi Saluran Distribusi Tenaga Listrik Secara umum, saluran tenaga Listrik atau saluran distribusi dapat
diklasifikasikan sebagai berikut: 2-2-1. Menurut nilai tegangannya: 2-2-1-1 Saluran distribusi Primer.
Terletak pada sisi primer trafo distribusi, yaitu antara titik Sekunder trafo substation (G.I.) dengan titik primer trafo distribusi. Saluran ini ber- tegangan menengah 20kV. Jaringan listrik 70 kV atau 150 kV, jika langsung melayani pelanggan , bisa disebut jaringan distribusi. 2-2-1-2 Saluran Distribusi Sekunder,
Terletak pada sisi sekunder trafo distribusi, yaitu antara titik sekunder dengan titik cabang menuju beban (Lihat Gambar 2-2) 2-2-2 Menurut bentuk tegangannya:
a. Saluran Distribusi DC (Direct Current) menggunakan sistem tegangan searah.
b. Saluran Distribusi AC (Alternating Current) menggunakan sistem tegangan bolak-balik.
2-2-3 Menurut jenis/tipe konduktornya: a. Saluran udara, dipasang pada udara terbuka dengan bantuan support
(tiang) dan perlengkapannya, dibedakan atas: - Saluran kawat udara, bila konduktornya telanjang, tanpa isolasi
pembungkus. - Saluran kabel udara, bila konduktornya terbungkus isolasi.
b. Saluran Bawah Tanah, dipasang di dalam tanah, dengan menggunakan kabel tanah (ground cable).
c. Saluran Bawah Laut, dipasang di dasar laut dengan menggunakan kabel laut (submarine cable)
2-2-4 Menurut susunan (konfigurasi) salurannya: a. Saluran Konfigurasi horisontal: Bila saluran fasa terhadap fasa yang lain/terhadap netral, atau saluran positip terhadap negatip (pada sistem DC) membentuk garis horisontal.
Gambar 2-3
Konfigurasi horisontal Gambar 2-4
Konfigurasi Vertikal
b. Saluran Konfigurasi Vertikal: Bila saluran-saluran tersebut membentuk garis vertikal
Sistem Distribusi Tenaga Listrik
14
c. Saluran konfigurasi Delta: Bila kedudukan saluran satu sama lain membentuk suatu segitiga (delta).
(a) (b)
(c) (d)
Gambar 2-5 Konfigurasi Delta
Gambar 2-6 (a) dan (b) Jaringan distribusi lintas bangunan (perhatikan pemasangan
kawat dekat bangunan dan diatas jalan raya)
Gambar 2-6 (c) dan (d). Jaringan distribusi lintas bangunan (perhatikan tarikan tiang ujung)
Sistem Distribusi Tenaga Listrik
15
(e) (f)
Gambar 2-9. Saluran Udara Lintas Alam
Gambar 2-7. Saluran Udara dengan konduktor kabel
Gambar 2-8. Saluran distribusi dimana saluran primer dan
sekunder terletak pada satu tiang
Gambar 2-6(e).Jaringan distribusi lintas bangunan (perhatikan tarikan tiang ujung di samping bangunan)
Gambar 2-6 (f). Jaringan distribusi lintas bangunan (perhatikan tarikan kawat vertikal disamping bangunan)
Sistem Distribusi Tenaga Listrik
16
2-2-5 Menurut Susunan Rangkaiannya Dari uraian diatas telah disinggung bahwa sistem distribusi di bedakan menjadi dua yaitu sistem distribusi primer dan sistem distribusi sekunder.
2-2-5-1 Jaringan Sistem Distribusi Primer Sistem distribusi primer diguna kan untuk menyalurkan tenaga listrik
dari gardu induk distribusi ke pusat-pusat beban. Sistem ini dapat mengguna kan saluran udara, kabel udara, maupun kabel tanah sesuai dengan tingkat keandalan yang diinginkan dan kondisi serta situasi lingkungan. Saluran distribusi ini direntangkan sepanjang daerah yang akan di suplai tenaga listrik sampai ke pusat beban. Terdapat bermacam-macam bentuk rangkaian jaringan distribusi primer.
1) Jaringan Distribusi Radial. Bila antara titik sumber dan titik bebannya hanya terdapat satu
saluran (line), tidak ada alternatif saluran lainnya. Bentuk Jaringan ini merupakan bentuk dasar, paling sederhana dan paling banyak digunakan. Dinamakan radial karena saluran ini ditarik secara radial dari suatu titik yang merupakan sumber dari jaringan itu,dan dicabang-cabang ke titik-titik beban yang dilayani.
Catu daya berasal dari satu titik sumber dan karena adanya penca-bangan-pencabangan tersebut, maka arus beban yang mengalir sepanjang saluran menjadi tidak sama besar.
Oleh karena kerapatan arus (beban) pada setiap titik sepanjang saluran tidak sama besar, maka luas penampang konduktor pada jaringan bentuk radial ini ukurannya tidak harus sama. Maksudnya, saluran utama (dekat sumber) yang menanggung arus beban besar, ukuran penampangnya relatip besar, dan saluran cabang-cabangnya makin ke ujung dengan arus beban yang lebih kecil, ukurannya lebih kecil pula. Spesifikasi dari jaringan bentuk radial ini adalah:
a). Bentuknya sederhana.(+) b). Biaya investasinya relatip murah.(+) c). Kualitas pelayanan dayanya relatip jelek, karena rugi tegangan dan
rugi daya yang terjadi pada saluran relatip besar.(-) d). Kontinyuitas pelayanan daya tidak terjamin, sebab antara titik
sumber dan titik beban hanya ada satu alternatif saluran sehingga bila saluran tersebut mengalami gangguan, maka seluruh rangkaian sesudah titik gangguan akan mengalami "black out" secara total.(-)
Untuk melokalisir gangguan, pada bentuk radial ini biasanya diperlengkapi dengan peralatan pengaman berupa fuse, sectionaliser, recloser, atau alat pemutus beban lainnya, tetapi fungsinya hanya mem- batasi daerah yang mengalami pemadaman total, yaitu daerah saluran sesudah/dibelakang titik gangguan, selama gangguan belum teratasi. Jadi,
Sistem Distribusi Tenaga Listrik
17
misalkan gangguan terjadi di titik F, maka daerah beban K, L dan M akan mengalami pemadaman total (Gambar 2-10). Jaringan distribusi radial ini memiliki beberapa bentuk modifikasi, antara lain:
(1). Radial tipe pohon. (2). Radial dengan tie dan switch pemisah. (3). Radial dengan pusat beban. (4). Radial dengan pembagian phase area.
(1) Jaringan Radial tipe Pohon Bentuk ini merupakan bentuk yang paling dasar. Satu saluran utama
dibentang menurut kebutuhannya, selanjutnya dicabangkan dengan saluran cabang (lateral penyulang) dan lateral penyulang ini dicabang-cabang lagi dengan sublateral penyulang (anak cabang). Sesuai dengan kerapatan arus yang ditanggung masing-masing saluran, ukuran penyulang utama adalah yang terbesar, ukuran lateral adalah lebih kecil dari penyulang utama, dan ukuran sub lateral adalah yang terkecil.
(2) Jaringan radial dengan tie dan switch pemisah. Bentuk ini merupakan modifikasi bentuk dasar dengan me-
nambahkan tie dan switch pemisah, yang diperlukan untuk mempercepat pemulihan pelayanan bagi konsumen, dengan cara menghubungkan area-area yang tidak terganggu pada penyulang yang bersangkutan, dengan penyulang di sekitarnya. Dengan demikian bagian penyulang yang terganggu dilokalisir, dan bagian penyulang lainnya yang "sehat" segera dapat dioperasikan kembali, dengan cara melepas switch yang terhubung ke titik gangguan, dan menghubungkan bagian penyulang yang sehat ke penyulang di sekitarnya.
DISTRIBUTION TRANSFORMER
Gambar 2-11. Komponen
Jaringan radial Gambar 2-10.
Jaringan radial tipe pohon
LAYANAN KONSUMEN
PENYULANG PRIMER
SUBTRANSMISI
SUMBER DAYA
DISTRIBUTIONSUBSTATION
RIL SEKUNDER
TRAFODISTRIBUSI
Sistem Distribusi Tenaga Listrik
18
(3). Jaringan radial tipe pusat beban.
Bentuk ini mencatu daya dengan menggunakan penyulang utama (main feeder) yang disebut "express feeder" langsung ke pusat beban, dan dari titik pusat beban ini disebar dengan menggunakan "back feeder" secara radial.
Gambar 2-12. Jaringan radial dengan tie dan switch
Gambar 2- 13. Jaringan radial tipe pusat beban
Sistem Distribusi Tenaga Listrik
19
(4) Jaringan radial dengan phase area Pada bentuk ini masing-masing fasa dari jaringan bertugas melayani
daerah beban yang berlainan. Bentuk ini akan dapat menimbulkan akibat kondisi sistem 3 fasa yang tidak seimbang (simetris), bila digunakan pada daerah beban yang baru dan belum mantap pembagian bebannya. Karenanya hanya cocok untuk daerah beban yang stabil dan penambahan maupun pembagian bebannya dapat diatur merata dan simetris pada setiap fasanya
2) Jaringan distribusi ring (loop).
Bila pada titik beban terdapat dua alternatip saluran berasal lebih dari satu sumber. Jaringan ini merupakan bentuk tertutup, disebut juga bentuk jaringan "loop". Susunan rangkaian penyulang membentuk ring, yang memungkinkan titik beban dilayani dari dua arah penyulang, sehingga kontinyuitas pelayanan lebih terjamin, serta kualitas dayanya menjadi lebih baik, karena rugi tegangan dan rugi daya pada saluran menjadi lebih kecil. Bentuk loop ini ada 2 macam, yaitu:
(a). Bentuk open loop: Bila diperlengkapi dengan normally-open switch, dalam keadaan
normal rangkaian selalu terbuka. (b). Bentuk close loop Bila diperlengkapi dengan normally-close switch, yang dalam
keadaan normal rangkaian selalu tertutup.
MAIN FEEDER (3 PHASA)
AREA BEBAN FASA R
AREA BEBAN FASA S
AREA BEBAN FASA T
SINGLE PHASA FEEDER
KE BEBAN
Gambar 2-14. Jaringan radial tipe phase area (kelompok fasa)
Sistem Distribusi Tenaga Listrik
20
Gambar 2-15. Jaringan Distribusi tipe Ring
Gambar 2-16. Jaringan Distribusi ring terbuka
Gambar 2-17. Jaringan Distribusi ring tertutup
Sistem Distribusi Tenaga Listrik
21
Pada tipe ini, kualitas dan kontinyuitas pelayanan daya memang lebih balk, tetapi biaya investasinya lebih mahal, karena memerlukan pemutus beban yang lebih banyak. Bila digunakan dengan pemutus beban yang otomatis (dilengkapi dengan recloser atau AVS),maka pengamanan dapat berlangsung cepat dan praktis, dengan cepat pula daerah gangguan segera beroperasi kembali bila gangguan telah teratasi. Dengan cara ini berarti dapat mengurangi tenaga operator. Bentuk ini cocok untuk digunakan pada daerah beban yang padat dan memerlukan keandalan tinggi.
3) Jaringan distribusi Jaring-jaring (NET) Merupakan gabungan dari beberapa saluran mesh, dimana
terdapat lebih satu sumber sehingga berbentuk saluran interkoneksi. Jaringan ini berbentuk jaring-jaring, kombinasi antara radial dan loop.
Gambar 2-18. Rangkaian Gardu Induk tipe Ring
Gambar 2-20. Jaringan Distribusi NET dengan Tiga penyulang Gardu Hubung
Distribution Transformer
Primary Tre Feeder
Gambar 2-19. Jaringan Distribusi NET
Substation Circuit
Bulk Power Source Bus
Distribution Transfprmer
Sistem Distribusi Tenaga Listrik
22
Titik beban memiliki lebih banyak alternatip saluran/penyulang, sehingga bila salah satu penyulang terganggu, dengan segera dapat digantikan oleh penyulang yang lain. Dengan demikian kontinyuitas penya-luran daya sangat terjamin. Spesifikasi Jaringan NET ini adalah:
1). Kontinyuitas penyaluran daya paling terjamin.(+) 2). Kualitas tegangannya baik, rugi daya pada saluran amat kecil.(+) 3). Dibanding dengan bentuk lain, paling flexible (luwes) dalam
mengikuti pertumbuhan dan perkembangan beban. (+ 4). Sebelum pelaksanaannya, memerlukan koordinasi perencanaan
yang teliti dan rumit. (-) 5). Memerlukan biaya investasi yang besar (mahal) (-) 6). Memerlukan tenaga-tenaga terampil dalam pengoperasian nya.(-)
Dengan spesifikasi tersebut, bentuk ini hanya layak (feasible) untuk melayani daerah beban yang benar-benar memerlukan tingkat keandalan dan kontinyuitas yang tinggi, antara lain: instalasi militer, pusat sarana komunikasi dan perhubungan, rumah sakit, dan sebagainya. Karena bentuk ini merupakan jaringan yang menghubungkan beberapa sumber, maka bentuk jaringan NET atau jaring-jaring disebut juga jaringan "interkoneksi".
Gambar 2-21. Jaringan Distribusi NET dilengkapi breaker pada bagian tengah masing-masing penyulang
Sistem Distribusi Tenaga Listrik
23
4) Jaringan distribusi spindle. Selain bentuk-bentuk dasar dari jaringan distribusi yang telah ada,
maka dikembangkan pula bentuk-bentuk modifikasi, yang bertujuan meningkatkan keandalan dan kualitas sistem. Salah satu bentuk modifikasi yang populer adalah bentuk spindle, yang biasanya terdiri atas maksimum 6 penyulang dalam keadaan dibebani, dan satu penyulang dalam keadaan kerja tanpa beban. Perhatikan gambar 2-22. Saluran 6 penyulang yang beroperasi dalam keadaan berbeban dinamakan "working feeder" atau saluran kerja, dan satu saluran yang dioperasikan tanpa beban dinamakan "express feeder".
Fungsi "express feeder" dalam hal ini selain sebagai cadangan pada saat terjadi gangguan pada salah satu "working feeder", juga berfungsi untuk memperkecil terjadinya drop tegangan pada sistem distribusi bersangkutan pada keadaan operasi normal. Dalam keadaan normal memang "express feeder" ini sengaja dioperasikan tanpa beban. Perlu diingat di sini, bahwa bentuk-bentuk jaringan beserta modifikasinya seperti yang telah diuraikan di muka, terutama dikembangkan pada sistem jaringan arus bolak-balik (AC).
5) Saluran Radial Interkoneksi Saluran Radial Interkoneksi yaitu terdiri lebih dari satu saluran radial tunggal yang dilengkapi dengan LBS/AVS sebagai saklar inerkoneksi. Masing-masing tipe saluran tersebut memiliki spesifikasi sendiri, dan agar lebih jelas akan dibicarakan lebih lanjut pada bagian lain. Pada dasarnya semua beban yang memerlukan tenaga listrik, menuntut kondisi pelayanan yang terbaik, misalnya dalam hal stabilitas tegangannya, sebab seperti telah dijelaskan, bila tegangan tidak nominal
Gambar 2-22. Jaringan distribusi Spindle
Sistem Distribusi Tenaga Listrik
24
dan tidak stabil, maka alat listrik yang digunakan tidak dapat beroperasi secara normal, bahkan akan mengalami kerusakan. Tetapi dalam prakteknya, seberapa besar tingkat pelayanan terbaik dapat dipenuhi, masih memerlukan beberapa pertimbangan, mengingat beberapa alasan. Digunakan untuk daerah dengan :
- Kepadatan beban yang tinggi - Tidak menuntut keandalan yang terlalu tinggi
Contoh: Daerah pinggiran kota, kampung, perumahan sedang.
Secara umum, baik buruknya sistem penyaluran dan distribusi tenaga listrik terutama adalah ditinjau dari hal-hal berikut ini: 1). Kontinyuitas Pelayanan yang baik, tidak sering terjadi pemutusan, baik
karena gangguan maupun karena hal-hal yang direncanakan. Biasanya, kontinyuitas pelayanan terbaik diprioritaskan pada beban-beban yang dianggap vital dan sama sekali tidak dikehendaki mengalami pemadaman, misalnya: instalasi militer, pusat pelayanan komunikasi, rumah sakit, dll.
2). Kualitas Daya yang baik, antara lain meliputi: - kapasitas daya yang memenuhi. - tegangan yang selalu konstan dan nominal. - frekuensi yang selalu konstan (untuk sistem AC).
Catatan: Tegangan nominal di sini dapat pula diartikan kerugian tegangan yang terjadi pada saluran relatif kecil sekali.
3). Perluasan dan Penyebaran daerah beban yang dilayani seimbang. Khususnya untuk sistem tegangan AC 3 fasa, faktor keseimbangan/
Gambar 2-23. Diagram satu garis Penyulang Radial Interkoneksi
Sistem Distribusi Tenaga Listrik
25
kesimetrisan beban pada masing-masing fasa perlu diperhatikan. Bagaimana pengaruh pembebanan yang tidak simetris pada suatu sistem distribusi, akan dibicarakan lebih lanjut dalam bagian lain.
4). Fleksibel dalam pengembangan dan perluaan daerah beban. Perencanaan sistem distribusi yang baik, tidak hanya bertitik tolak pada
kebutuhan beban sesaat, tetapi perlu diperhatikan pula secara teliti mengenai pengembangan beban yang harus dilayani, bukan saja dalam hal penambahah kapasitas dayanya, tetapi juga dalam hal perluasan daerah beban yang harus dilayani.
5). Kondisi dan Situasi Lingkungan. Faktor ini merupakan pertimbangan dalam perencanaan untuk menentukan tipetipe atau macam sistem distribusi mana yang sesuai untuk lingkungan bersangkutan, misalnya tentang konduktornya, konfigurasinya, tata letaknya, dsb. termasuk pertimbangan segi estetika (keindahan) nya.
6). Pertimbangan Ekonomis. Faktor ini menyangkut perhitungan untung rugi ditinjau dari segi ekonomis, baik secara komersiil maupun dalam rangka penghematan anggaran yang tersedia.
2-2-5-2 Jaringan Sistem Distribusi Sekunder Sistem distribusi sekunder digunakan untuk menyalurkan tenaga
listrik dari gardu distribusi ke beban-beban yang ada di konsumen. Pada sistem distribusi sekunder bentuk saluran yang paling banyak digunakan ialah sistem radial. Sistem ini dapat menggunakan kabel yang berisolasi maupun konduktor tanpa isolasi. Sistem ini biasanya disebut sistem tegangan rendah yang langsung akan dihubungkan kepada konsumen/pemakai tenaga listrik dengan melalui peralatan-peralatan sbb:
1) Papan pembagi pada trafo distribusi, 2) Hantaran tegangan rendah (saluran distribusi sekunder). 3) Saluran Layanan Pelanggan (SLP) (ke konsumen/pemakai) 4) Alat Pembatas dan pengukur daya (kWH. meter) serta fuse atau
pengaman pada pelanggan. Komponen saluran distribusi sekunder seperti ditunjukkan pada gambar 2-24 berikut ini.
Gambar 2-24. Komponen sistem distribusi
Keterangan : PMS = Pemisah TD = Trafo Distribusi FC = Fuse Cabang PMT = Pemutus SU = Saklar Utama FCO = Fuse Cut Out SC = Saklar Cabang
PMT RIL-TT
SUPMS PMS
RIL-TR
TD FCO
SC FC
PELA
YAN
AN
K
ON
SUM
EN
Sistem Distribusi Tenaga Listrik
26
Selanjutnya konstruksi hantaran tegangan rendah diuraikan pada bab IV sedang Alat Ukur dan Pembatas diuraikan pada bab III.
2-3 Tegangan Sistem Distribusi Sekunder Ada bermacam-macam sistem tegangan distribusi sekunder menurut
standar; (1) EEI : Edison Electric Institut, (2) NEMA (National Electrical Manufactures Association). Pada dasarnya tidak berbeda dengan sistem distribusi DC, faktor utama yang perlu diperhatikan adalah besar tegangan yang diterima pada titik beban mendekati nilai nominal, sehingga peralatan/beban dapat dioperasikan secara optimal. Ditinjau dari cara pengawatannya, saluran distribusi AC dibedakan atas beberapa macam tipe, dan cara pengawatan ini bergantung pula pada jumlah fasanya, yaitu:
1. Sistem satu fasa dua kawat 120 Volt 2. Sistem satu fasa tiga kawat 120/240 Volt 3. Sistem tiga fasa empat kawat 120/208 Volt 4. Sistem tiga fasa empat kawat 120/240 Volt 5. Sistem tiga fasa tiga kawat 240 Volt 6. Sistem tiga fasa tiga kawat 480 Volt 7. Sistem tiga fasa empat kawat 240/416 Volt 8. Sistem tiga fasa empat kawat 265/460 Volt 9. Sistem tiga fasa empat kawat 220/380 Volt
Di Indonesia dalam hal ini PT. PLN menggunakan sistem tegangan 220/380 Volt. Sedang pemakai listrik yang tidak menggunakan tenaga listrik dari PT. PLN, menggunakan salah satu sistem diatas sesuai dengan standar yang ada. Pemakai listrik yang dimaksud umumnya mereka bergantung kepada negara pemberi pinjaman atau dalam rangka kerja sama, dimana semua peralatan listrik mulai dari pembangkit (generator set) hingga peralatan kerja (motor-motor listrik) di suplai dari negara pemberi pinjaman/kerja sama tersebut. Sebagai anggota, IEC (International Electrotechnical Comission), Indonesia telah mulai menyesuaikan sistem tegangan menjadi 220/380 Volt saja, karena IEC sejak tahun 1967 sudah tidak mencantumkan lagi tegangan 127 Volt. (IEC Standard Voltage pada Publikasi nomor 38 tahun 1967 halaman 7 seri 1 tabel 1). Diagram rangkaian sisi sekunder trafo distribusi untuk masing-masing sistem tegangan tersebut ditunjukkan pada gambar berikut ini:
2-3-1 Sistem distribusi satu fasa dengan dua kawat.
(a) (b)
120V 120V
Gambar 2-25. Sistem satu fasa dua kawat tegangan 120Volt
Sistem Distribusi Tenaga Listrik
27
120V
208V
208V
120V
120V
240V
240V
Tipe ini merupakan bentuk dasar yang paling sederhana, biasanya digunakan untuk melayani penyalur daya berkapasitas kecil dengan jarak pendek, yaitu daerah perumahan dan pedesaan. Ditinjau dari sisi sekunder trafo distribusinya, tipe ini ada 2(dua) macam, seperti ditunjukkan apada gambar 3-25. 2-3-2 Sistem distribusi satu fasa dengan tiga kawat. Pada tipe ini, prinsipnya sama dengan sistem distribusi DC dengan tiga kawat, yang dalam hal ini terdapat dua alternatif besar tegangan. Sebagai saluran “netral” disini dihubungkan pada tengah belitan (center-tap) sisi sekunder trafo, dan diketanahkan, untuk tujuan pengamanan personil. Tipe ini untuk melayani penyalur daya berkapasitas kecil dengan jarak pendek, yaitu daerah perumahan dan pedesaan.
2-3-3 Sistem distribusi tiga fasa empat kawat tegangan 120/240 Volt
Tipe ini untuk melayani penyalur daya berkapasitas sedang dengan jarak pendek, yaitu daerah perumahan pedesaan dan perdagangan ringan, dimana terdapat dengan beban 3 fasa
2-3-4 Sistem distribusi tiga fasa empat kawat tegangan 120/208 Volt
Untuk rangkaian seperti diatas terdapat pula sistem tegangan 240/416 Volt dan atau tegangan 265/460 Volt.
Gambar 2-27. Sistem distribusi tiga fasa empat kawat tegangan 120/240 Volt
CT 120 V
120V 240V
Gambar 2-26. Sistem satu fasa tiga kawat tegangan 120/240 Volt
Gambar 2-28. Sistem distribusi tiga fasa empat kawat tegangan 120/208 Volt
Sistem Distribusi Tenaga Listrik
28
220V
380V
380V
2-3-5 Sistem distribusi tiga fasa dengan tiga kawat
Tipe ini banyak dikembangkan secara ekstensif. Dalam hal ini rangkaian tiga fasa sisi sekunder trafo dapat diperoleh dalam bentuk rangkaian delta (segitiga) ataupun rangkaian wye (star/bintang).
Diperoleh dua alternatif besar tegangan, yang dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan adanya pembagian seimbang antara ketiga fasanya. Untuk rangkaian delta tegangannya bervariasi yaitu 240 Volt, dan 480 Volt. Tipe ini dipakai untuk melayani beban-beban industri atau perdagangan.
2-3-6 Sistem distribusi tiga fasa dengan empat kawat
Pada tipe ini, sisi sekunder (output) trafo distribusi terhubung star,
dimana saluran netral diambil dari titik bintangnya. Seperti halnya pada sistem tiga fasa yang lain, di sini perlu diperhatikan keseimbangan beban antara ketiga fasanya, dan disini terdapat dua alternatif besar tegangan. 2-3-7 Ketidaksimetrisan beban
Dalam kondisi ideal dimana beban benar-benar terbagi rata (simetris) pada ketiga fasanya, maka arus yang lewat pada saluran netral adalah benar-benar “netral´(nol), yang artinya saluran netral ini tidak dilalui arus. Karenanya dalam pelaksanaan pengoperasiannya, saluran netral pada tipe star dibuat dengan ukuran yang lebih kecil dari ukuran kawat-kawat fasanya. Tipe ini dipakai untuk melajani beban-beban perumahan, perdagangan dan Industri Generator AC tiga fasa, pada dasarnya adalah serupa dengan tiga generator satu fasa dengan daya yang sama (P3φ = 3 x P1φ), yang dirancang menyatu secara rigid (kompak), dengan tata letak masing-masing kumparan berbeda sudut (listrik) sebesar 120o. Jadi, misalkan sebuah generator 3φ
Gambar 2-30. Sistem distribusi tiga fasa empat kawat 220/380 Volt
416V
416V
240V
240V
Gambar 2-29. Sistem distribusi tiga fasa tiga kawat
Sistem Distribusi Tenaga Listrik
29
berkapasitas nominal bebannya 10 ampere, pada dasarnya adalah sama dengan tiga generator 1φ masing-masing berkapasitas 10 ampere, yang dijadikan satu. Jika dibandingkan pada kapasitas daya yang sama, misalkan sebuah generator AC 3φ berkapasitas 30 kVA (total) dengan generator AC 1φ berkapasitas 30 kVA akan didistribusikan pada 3 berkas kumparan daya, (katakan bebannya simetris), masing-masing berkas menanggung 10 kVA. Pada tipe 1φ, daya sebesar 30 kVA ini seluruhnya ditanggung oleh satu berkas kumparan daya. Dalam praktek, sistem 3 fasa tidak selalu beroperasi pada kondisi arus beban simetris, baik pada pembangkit maupun pada penyalurannya. Pada dasarnya, ada 4 sumber penyebab terjadinya ketidak simetrisan sistem 3 fasa ini, yaitu:
2-3-7-1 Tidak simetris tegangan sejak pada sumbernya: Tegangan tak simetris pada output generator 3 fasa bisa saja terjadi
(walaupun jarang) karena kesalahan teknis pada ketiga berkas kumparan dayanya (jumlah lilitan atau resistansi).
2-3-7-2 Tidak simetris tegangan pada salurannya: Hal demikian dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
1) Konfigurasi ketiga saluran secara total total tidak simetris, sehingga total kapasitansinya tidak simetris. Keadaan demikian dapat terjadi pada penyaluran jarak jauh dan bertegangan tinggi, dimana jarak rata-rata masing-masing saluran fasa terhadap tanah tidak sama.
2) Resistansi saluran tidak sama karena jenis bahan konduktor yang berbeda (besar R dipengaruhi oleh besar ⌠ ).
3) Resistansi saluran tidak sama karena ukuran konduktor tidak sama (besar R dipengaruhi oleh besar q).
4) Resistansi saluran tidak sama karena jarak antara masing-masing saluran fasa dengan beban tidak sama (besar R dipengaruhi oleh jarak l).
2-3-7-3 Tidak simetris pada resistansi bebannya: Karena besar I (arus beban) ditentukan oleh besar R(beban), maka
pada keadaan 3φ: RR ≠ RS ≠ RT, maka arus bebannya: IR ≠ IS ≠ IT. Akibat lanjutnya adalah: bila resistansi saluran dianggap sama dengan R, maka rugi tegangan yang terjadi pada sistem 3φ adalah IRR ≠ ISR ≠ ITR atau VR ≠ VS ≠ VT dan rugi daya IR2R ≠ IS2R ≠ IT2R atau PR ≠ PS ≠ PT sehingga: V(T)R ≠ V(T)S ≠ V(T)T dimana V(T) = tegangan pada sisi terima (konsumen). Kondisi tak simetris pada tegangan sisi terima akibat tidak simetrisnya beban ini adalah suatu hal yang paling sering terjadi dalam praktek, antara lain oleh adanya sambungan-sambungan di luar perhitungan dan perencanaan. Upaya teknis memang perlu dilakukan, agar diperoleh keadaan pembebanan yang simetris. Pada sistem 3 fasa yang menggunakan saluran netral (baca saluran nol), dalam keadaan beban simetris maka arus yang lewat saluran nol adalah benar-benar nol (netral), tetapi bila terjadi keadaan tak simetris, maka sebagian arus (berupa arus resultan) akan lewat saluran netral ini, sehingga saluran tersebut menjadi tidak netral lagi.
Sistem Distribusi Tenaga Listrik
30
2-3-7-4 Tidak sama besar faktor daya dari bebannya: Keadaan demikian bisa terjadi, misalnya bila sistem 3 fasa dibebani
seperti berikut: - Fasa R dibebani (1φ) beban resistif murni - Fasa S dibebani motor 1φ dengan p.f. = 0,8 mengikut. - Fasa T dibebani motor 1φ dengan p.f. = 0,6 mengikut. - Fasa RST dibebani motor 3φ dengan p.f. = 0,8 mengikut. Dengan pembebanan tersebut berarti arus beban akan tidak simetris. 2-4 Gardu Distribusi
Gardu listrik pada dasarnya adalah rangkaian dari suatu perlengkapan hubung bagi ; a) PHB tegangan menengah; b) PHB tegangan rendah. Masing-masing dilengkapi gawai-gawai kendali dengan komponen proteksinya. Jenis-jenis gardu listrik atau gardu distribusi didesain berdasarkan maksud dan tujuan penggunaannya sesuai dengan peraturan Pemda setempat, yaitu: 1) Gardu Distribusi konstruksi beton (Gardu Beton); 2) Gardu Distribusi konstruksi metal clad (Gardu besi); 3a) Gardu Distribusi tipe tiang portal, 3b) Distribusi tipe tiang cantol (Gardu Tiang); dan 4a) Gardu Distribusi mobil tipe kios, 4b) Gardu Distribusi mobil tipe trailer (Gardu Mobil).
Komponen-komponen gardu: a) PHB sisi tegangan rendah; b) PHB pemisah saklar daya); c) PHB pengaman transformator); d) PHB sisi tegangan rendah; e) Pengaman tegangan rendah; f) Sistem pembumian; g) alat-alat indikator.
Instalasi perlengkapan hubung bagi tegangan rendah berupa PHB TR atau rak TR terdiri atas 3 bagian, yaitu : 1) Sirkit masuk + sakelar; 2) Rel pembagi; 3) Sirkit keluar + pengaman lebur maksimum 8 sirkit
Spesifikasi mengikuti kapasitas transformator distribusi yang dipakai.
Instalasi kabel daya dan kabel kontrol, yaitu KHA kabel daya antara kubikel ke transformator minimal 125 % arus beban nominal transformator. Pada beban konstruksi memakai kubikel TM single core Cu : 3 x 1 x 25 mm2 atau 3x1x35mm2. Antara transformator dengan Rak TR memakai kabel daya dengan KHA 125 % arus nominal. Pada beberapa instalasi memakai kabel inti tunggal masingmasing kabel perfasa, Cu 2 x 3 x 1 x 240 mm2 + 1 x 240 mm2.
Gambar 2-31. Contoh Gambar Monogram Gardu Distribusi
Sistem Distribusi Tenaga Listrik
31
Instalasi lain yang ada pada gardu distribusi adalah Instalasi penerangan, terdiri dari; 1) Instalasi alat pembatas dan pengukur; 2) Inststalasi kabel scada untuk kubikel dengan motor kontrol; 3) Instalasi pengaman pelanggan untuk APP pelanggan tegangan menengah
Prosedur uji laik instalasi gardu; Sebelum dioperasikan instalasi
gardu distribusi harus dilakukan uji laik yang meliputi:
1). Uji verifikasi rencana - Meneliti kesesuaian hasil pelaksanaan dengan rancangan
bahan referensi adalah persyaratanpersyaratan teknis pada rancangan surat perintah kerja.
- Meneliti kesesuaian spesifikasi teknis dengan material yang terpasang.
2). Uji fisik hasil pelaksanaan. - Meneliti apakah hasil pelaksanaan telah memenuhi per-
syaratan fisik hasil pekerjaan (kokoh, tidak goyang) tekukan, belokan kabel clan lain-lain.
- Meneliti mekanisme kerja peralatan. - Meneliti kebenaran pengkabelan, pengawatan instalasi listrik. - Meneliti kekencangan ikatan-ikatan mur, baut, konektor dan
lain-lain. - Meniliti kabel-kabel instalasi tidak menahan beban mekanik
selain beban sendiri. - Meneliti pengkabelan (wiring) instalasi kontrol.
3). Uji Ketahanan Isolasi - Melakukan uji ketahanan isolasi dengan alat megger pada tiap
antar fasa clan fasa tanah (referensi PUIL 1 volt = 1 kilo ohm) pada sisi TM clan TR.
- Uji dilakukan juga pada transformator. 4) Uji ketahanan Impulse
Melakukan uji withstand test 50 k J per 1 menit.
Gambar 2-32. Penampang Fisik Gardu Distribusi
Sistem Distribusi Tenaga Listrik
32
5). Uji Power Frekuensi .... Melakukan uji tegangan 24 kV selama 15 menit.
6). Uji alat proteksi -Uji fisik pengaman lebur dengan multi meter -Uji Rak proteksi (jika ada)
7). Uji alat-alat kontrol - Setelah dioperasikan uji unjuk kerja alat-alat kontrol (lampu, voltmeter, ampere meter): Hasil uji laik didokumenkan untuk izin operasional.
8). Instalasi untuk pelanggan tegangan menengah, hanya ditambah: - Satu sel kubikel transformator tegangan - Satu sel kubikel sambungan pelanggan dengan fasilitas: - Circuit breaker yang bekerja etas dater batas arus nominal.
Daya tersambung pelanggan. - Transformator arus.
- Satu sel kubikel untuk sambungan kabel milik pelanggan - Satu set alat ukur ( KWH meter, KVARH meter)
- Satu set relai pembatas beban.
9). Spesifikasi teknis den ketentuan instalasinya same dengan ketentuan instalasi sel kubikel lain.
10). Uji opersional dilaksanakan dengan tambahan, uji untuk kerja circuit breaker den relai pembatas pelanggan.
Gambar 2-33. Bagan satu garis pelanggan TM
Contoh-cotoh tipe-tipe sel kubikel sambungan pelanggan Alsthom : PGDb. PGDt Merlin Gerin : DM12, DM 22
Sistem Distribusi Tenaga Listrik
33
2-4-1 Gardu Beton Yaitu gardu distribusi yang bangunan pelindungnya terbuat dari
beton (campuran pasir, batu dan semen). Gardu beton termasuk `gardu jenis pasangan dalam, karena pada umumnya semua peralatan peng-hubung/pemutus, pemisah dan trafo distribusi terletak di dalam bangunan beton. Dalam pembangunannya semua peralatan tersebut di disain dan diinstalasi di lokasi sesuai dengan ukuran bangunan gardu. Gambar 3-37 memperlihatkan sebuah gardu distribusi konstruksi beton.
8
6 4
5
7
Gambar 2-35. Bangunan Gardu beton
1 2 3 Keterangan : 1. Kabel masuk-pemisah atau
sakelar beban (load break) 2. Kabel keluar-sakelar beban (load
break) 3. Pengaman transformator-sakelar
beban+pengaman lebur. 4. Sakelar beban sisi TR. 5. Rak TR dengan 4 sirkit bekan. 6. Pengaman lebur TM (HRC-Fuse) 7. Pengaman lebur TR(NH - Fuse) 8. Transformator.
Gambar 2-34. Bagan satu garis Gardu Beton
Sistem Distribusi Tenaga Listrik
34
Ketentuan teknis komponen gardu beton, komponen tegangan menengah (contoh rujukan PHB tegangan menengah), yaitu; a) Tegangan perencanaan 25 kV; b) Power frekuensi withstand voltage 50 kV untuk 1 menit; c) Impulse withstand voltage 125 kV; d) Arus nominal 400A; e) Arus nominal transformator 50A; f) Arus hubung singkat dalam 1 detik 12,5 kA; g) Short circuit making current 31,5 kA. Komponen tegangan rendah (contoh rujukan PHB tegangan rendah), yaitu;
a) Tegangan perencanaan 414 Volt(fasa-fasa); b) Power frekuensi withstand 3 kV untuk 1 menit test fasa-fasa; c) Impulse withstand voltage 20 kV; d) Arus perencanaan rel/busbar 800 A, 1.200 A, 1.800 A; e) Arus perencanaan sirkit keluar 400A; f) Test ketahanan tegangan rendah.
Harga Efektif (RMS)
Rel (Waktu 0,5 detik) Peak 800 A 16 kA 32 kA 1200 A 25 kA 52 kA
1800 A 32 kA 72 kA
Gambar 3-36. Bardu Besi
2-4-2 Gardu metal clad (Gardu besi) Yaitu gardu distribusi yang bangunan pelindungnya terbuat dari
besi. Gardu besi termasuk gardu jenis pasangan dalam, karena pada umumnya semua peralatan penghubung/pemutus, pemisah dan trafo distribusi terletak di dalam bangunan besi. Semua peralatan tersebut sudah di instalasi di dalam bangunan besi, sehingga dalam pembangunan nya pelaksana pekerjaan tinggal menyiapkan pondasinya saja. Gambar 2-36 memperlihatkan sebuah gardu distribusi berupa gardu besi berbentuk kios.
Sistem Distribusi Tenaga Listrik
35
2-4-3 Gardu Tiang Tipe Portal. Gardu Tiang, yaitu gardu distribusi yang bangunan pelindungnya/
penyangganya terbuat dari tiang. Dalam hal ini trafo distribusi terletak di bagian atas tiang. Karena trafo distribusi terletak pada bagian atas tiang, maka gardu tiang hanya dapat melayani daya listrik terbatas, mengingat berat trafo yang relatif tinggi, sehingga tidak mungkin menempatkan trafo berkapasitas besar di bagian atas tiang (± 5 meter di atas tanah). Untuk gardu tiang dengan trafo satu fasa kapasitas yang ada maksimum 50 KVA, sedang gardu tiang dengan trafo tiga fasa kapasitas maksimum 160 KVA (200 kVA). Trafo tiga fasa untuk gradu tiang ada dua macam, yaitu trafo 1x3 fasa dan trafo 3x1fasa. Gambar 3-39 memperlihatkan sebuah gardu distribusi tiang tipe portal lengkap dengan perlengkapan proteksinya dan panel distribusi tegangan rendah yang terletak di bagian bawah tiang (tengah).
2-4-3-1 Bangunan fisik Gardu Portal Gardu portal adalah gardu listrik tipe terbuka (outdoor) yang
memakai konstruksi tiang/menara kedudukan transformator minimal 3 meter diatas platform. Umumnya memakai tiang beton ukuran 2x500 daN.
- Perlengkapan peralatan terdiri atas : Fuse cut out Arrester lighting Transformer type 250, 315, 400 WA Satu lemari PHB tegangan rendah maksimal 4 jurusan Isolator tumpu atau gantung
Gambar 2-37. Gardu tiang tipe portal dan Midel Panel
Sistem Distribusi Tenaga Listrik
36
Sistem pentanahan
- Lemari PHB TR dipasang minimal 1,2 meter diatas permukaan tanah atau 1,5 meter pada daerah yang sering terkena banjir. Pada beberapa tempat gardu portal juga dipasang trafo arus untuk pengukuran alat ukur pelanggan-pelanggan tegangan rendah.
2-4-4 Gardu Tiang Tipe Cantol.
2-4-4-1 Bangunan fisik Gardu tipe Cantol - Gardu cantol adalah type.gardu listrik dengan transformator yang
dicantolkan pada tiang listrik besamya kekuatan tiang minimal 500 daN. - Instalasi gardu dapat berupa :
• 1 Cut out fused • 1 lighting arrester. • 1 panel PHB tegangan rendah dengan 2 jurusan atau transfor- mator completely self protected (CSP - Transformator) Lihat contoh gambar konstruksi gardu cantol PT. PLN (Persero)
2-4-4-2 Sambungan Gardu Tiang Tipe Cantol - Gardu cantol 1 fasa dengan transformator CSP (completely self
protected) untuk pelayanan satu fasa.
- Untuk pelayanan sistem 3 fasa memakai 3 buah trafo 1 fasa dengan titik netral di gabungkan dari tiap-tiap transformator menjadi satu.
- Instalasi dalam PHB terbagi atas 6 bagian utama.
o Instalasi switch gear tegangan menengah o Instalasi switch gear tegangan rendah o Instalasi transformator o Instalasi kabel tenaga dan kabel kontrol o Instalasi pembumian o Bangunan fisik gardu.
Keterangan Gambar 2-38: 1. Arrester. 2. Proteksi cut out fused 3. Trafo Distribusi 4. Sakelar beban tegangan
rendah 5. PHB tegangan rendah 6. Sirkit keluar dilengkapi
pengaman lebur (NH. Fuse)
Gambar 2-38. Bagan satu garis Gardu tiang tipe portal
Sistem Distribusi Tenaga Listrik
37
Instalasi Pembumian - Instalasi pembumian pada gardu berdasarkan ketentuan yang diber-
lakukan setempat. Tujuan utamanya adalah mendapatkan nilai pentanahan elektroda maksimum 1 Ohm
- Jenis-jenis Elektroda (lihat PUIL 2000 Bab III).
Gambar 2-40. Gardu tiang tiga fasa tipe Cantol
L1 L2
Gambar 2-39. Bagan satu garis Gardu tiang tipe Cantol
Keterangan 1. Transformator 2. Sirkit akhir 2 fasa 3. Arrester 4. Cut out fused, sakelar beban
TR sudah terpasang di dalam transformator.
Catatan EL1 - N = 220 Volt
EL2 - N = 220 Vol EL1 - EL 2 = 440 Volt
SUTM
L1 L2
Sistem Distribusi Tenaga Listrik
38
Contoh
Instalasi pembumian di PT. PLN Distribusi Jakarta Raya & Tangerang kabel 1 x 50 mm2 Cu digelar dibawah fondasi melingkar tertutup. Pada beberapa titik tiap-tiap 1 meter dikeluarkan sebagai terminal pembumian. Kabel ini berfungsi juga sebagai ikatan penyama potensial.
Contoh Penggunaan elektroda batang pada gardu distribusi: - Memakai elektroda dengan kedalaman 3-6 meter. - Jarak tanam minimal 2 meter atau sejarak 1 x panjang elektroda. - Pada terminal keluar harus diberi bak kontrol untuk melakukan
pengukuran tahanan tanah.
Ikatan Pembumian - Semua bagian-bagian konduktif terbuka clan bagian konduktif extra pada
gardu dihubungkan dengan penghantar ke ikatan penyama potensial pembumian.
- Titik netral sistem tegangan rendah pada terminal netral transformator, pada Rak PNB-TR dibumikan, dihubungkan pada elektroda pembumian.
- Klem pengikat harus terbuat dari bahan tahan korosi minimal memakai baut ukuran 10 mm2.
Gambar 2-42. Detail Pemasangan Elektrode Pentanahan
Gambar 2-41. Elektrode Pentanahan
Elektrode Pentanahan
Sistem Distribusi Tenaga Listrik
39
Keterangan
• Elektroda pembumian grid CU 1 x 50 mm2 digelar di bawah ponclasi gardu. • Pada titik-titik tertentu dikeluarkan setinggi 30 cm untuk terminal pembumian. • Penghantar terminal memakai CU 1 x 16 mm2 untuk BKT. CU 1 x 50 mm2 untuk
Netral Transformator BKT, Transformator dan Rak TR.
Konstruksi penunjang. • Beberapa konstruksi penunjang terdapat pada kelengkapan
konstruksi gardu yang kebutuhannya disesuaikan setempat. • Kabel Tray harus terbuat dari bahan anti korosif untuk ' keperluan
tiap-tiap 3 meter jalur kabel. • Klem kabel untuk memperkuat dudukan kabel pada ikatan
dinamis atau kabel tray bisa terbuat dari kayu (Support cable). - bolt clamp - Spice plate - plate bar - Collar- penjepit kabel pada Rak TR/TM. - Fisser ukuran 10 mm2 panjang 60 mm2, 120 mm2 - Insulating bolt, baut dilapisi nilon, makrolon. - Insulating slim, bahan bakelit, nilon, makrolon. - Terminal hubung, plat dibawah sel TM. - Clampping connector 0 9 mm2, 13 mm2, 17 mm2. - T- connector lunimog-clamp terbuat dari Cu. - Angle clamp connector (knee-konektor) - Connecting blok terbuat dari tembaga - Straight clamp connector
Untuk konstruksi pemasangan contoh pada standard konstruksi instalasi gardu PT. PLN (Persero).
2-4-5 Gardu Mobil Yaitu gardu distribusi yang bangunan pelindungnya berupa sebuah
mobil (diletakkan diatas mobil), sehingga bisa dipindah-pindah sesuai
Gambar 2-43. Diagram Instalasi Pembumian Gardu Distribusi
Sistem Distribusi Tenaga Listrik
40
dengan tempat yang membutuhkan. Oleh karenanya gardu mobil ini pada umumnya untuk pemakaian sementara(darurat), yaitu untuk mengatasi kebutuhan daya yang sifatnya temporer.
Secara umum ada dua jenis gardu mobil, yaitu pertama gardu mobil jenis pasangan dalam (mobil boks) dimana semua peralatan gardu berada di dalam bangunan besi yang mirip dengan gardu besi. Kedua, gardu mobil jenis pasangan luar, yaitu gardu yang berada diatas mobil trailer, sehingga bentuk pisiknya lebih panjang dan semua peralatan penghubung/pemutus, pemisah dan trafo distribusi tampak dari luar. Gambar 2-44 memperlihatkan sebuah gardu distribusi berupa gardu mobil pasangan luar berada diatas trailer. Gardu distribusi jenis trailer ini umumnya berkapasitas lebih besar daripada yang jenis mobil. Hal ini bisa dilihat dari konstruksi peralatan penghubung yang digunakan.
Pada setiap gardu distribusi umumnya terdiri dari empat ruang (bagian) yaitu, bagian penyambungan/pemutusan sisi tegangan tinggi,
bagian pengukuran sisi tegangan tinggi, bagian trafo distribusi dan bagian panel sisi tegangan rendah. Keterangan gambar:
1. Saklar pemisah 6. Pengubah tap 11. Saklar Pemisah 2. Penyalur Petir 7. Pemutus 12. Poros berganda 3. Pemutus 8. Kotak kontrol 13. Gudang peralatan 4. Isolator 9. Trafo bantu 5. Transformator 10. Baterai Nikad
Pada gardu beton dan gardu metal bagian-bagian tersebut tersekat satu dengan lainnya, sedang pada gardu tiang panel distribusi tegangan rendah diletakkan pada bagian bawah tiang. Pada gardu distribusi, sistem pengaman yang digunakan umumnya berupa arrester untuk mengantipasi tegangan lebih (over voltage), kawat tanah (ground wire) untuk melindungi saluran fasa dari sambaran petir dan sistem pentanahan untuk menetralisir muatan lebih, serta sekring pada sisi tegangan tinggi (fuse cut out) untuk memutus rangkaian jika terjadi arus lebih (beban lebih).
Gambar 2-44. Gardu mobil
Sistem Distribusi Tenaga Listrik
41
Secara visual "Fuse Cut Out" ini dari bawah (jauh) tampak sedang on atau off. Arrester dipasang di bagian luar gardu distribusi, yaitu pada SUTM tempat penyam-bungan ke gardu distribusi. "Fuse cut out" dipasang dekat arrester atau bisa juga dipasang di dalam gardu, jika jarak antara titik penyambungan dan gardu distribusi relatif jauh dan saluran cabang menuju gardu distri-busi menggunakan kabel tanah. Untuk gardu tiang dan gardu mobil "Fuse Cut Out" di pasang pada bagian atas tiang terdekat (titik jumper). Gambar 2-45 memperlihat kan sebuah pemutus beban 20 kV tipe "Fuse Cut out"
2-5 Trafo Distribusi 2-5-1 Trafo Buatan Indonesia
Trafo distribusi yang digunakan di Indonesia saat ini pada umumnya adalah trafo produksi dalam negeri. Ada lima pabrik trafo di Indonesia yaitu:
Gambar 2-45. Pemutus beban 20 kV tipe "Fuse Cut out"
Gambar 2-46. Trafo distribusi kelas 20 kV
Keterangan-keterangan gambar 2-46, adalah: 1. Rele Buchcolz 6. Sumbat pengeluaran minyak 2. Indikator permukaan minyak 7. Pelat-nama 3. Penapas Pengering 8. Apitan untuk hubungan tanah 4. Untuk pembukaan 9. Kantong-thermometer 5. lubang untuk tarikan 10. Alat untuk merubah kedudukan tap
Sistem Distribusi Tenaga Listrik
42
Trafo distribusi yang digunakan di Indonesia saat ini pada umumnya adalah trafo produksi dalam negeri. Ada lima pabrik trafo di Indonesia yaitu: PT. UNINDO, PT. TRAFINDO dan PT. ASATA di Jakarta; PT. MURAWA di Medan : PT. Bambang Djaja di Surabaya. Ditinjau dari jumlah fasanya trafo distribusi ada dua macam, yaitu trafo satu fasa dan trafo tiga fasa.
Trafo tiga fasa mempunyai dua tipe yaitu tipe tegangan sekunder ganda dan tipe tegangan sekunder tunggal. Sedang trafo satu fasa juga mempunyai dua tipe yaitu tipe satu kumparan sekunder dan tipe dua kumparan sekunder saling bergantung, yang di kenal dengan trafo tipe "NEW JEC". Gambar 2-46 memperlihatkan sebuah trafo distribusi tiga fasa kelas 20 kV produksi PT. UNINDO Jakarta menurut standarisasi DIN, Jerman Barat. Bak trafo dapat diisi dengan minyak trafo biasa atau askarel (suatu bahan buatan) dan kelas ini untuk kapasitas daya lebih kecil dari 1000 kVA.
2-5-2 Trafo Standar "NEW JEC"
Keterangan gambar 2-47: BH = Primarry Bushing High Pc = Primarry coil BL = Secondarry Bushing Low Sc = Secondarry coil Br = Breaker Switch Ar = Arrester PF = Power Fuse
Dengan mengubah posisi "tap changer" tegangan sisi sekunder dapat diatur dari 115 Volt sampai dengan 133 Volt. Keistimewaan trafo tipe New Jec ialah setiap fasa terdiri dari satu tabung dapat diinstalasi untuk mendapatkan dua sistem tegangan, yaitu sistem 127 Volt dan sistem 220 Volt,
Gambar 2-47. Hubungan dalam trafo distribusi tipe "New Jec"
Sistem Distribusi Tenaga Listrik
43
Gambar 2-49. Sistem satu fasa dua kawat 220 Volt
Gambar 2-50. Sistem satu fasa tiga kawat 127 Volt
P N
P
Gambar 2-48. Sistem satu fasa dua kawat 127 Volt
Sistem Distribusi Tenaga Listrik
44
Gambar 2-51. Sistem tiga fasa empat kawat 127/220 Volt
Gambar 2-52. Sistem tiga fasa empat kawat 220/380 Volt
Sistem Distribusi Tenaga Listrik
45
2-5-3 Bank Trafo
2-5-3-1 Bank trafo dengan ril sekunder Yang dimaksud dengan bank trafo ialah menghubungkan paralel
tegangan pada sisi sekunder sejumlah trafo, yang semuanya disambungkan dengan jaringan sisi primer yang sama. Gambar 2/53-55 memperlihatkan beberapa model bank trafo (Transformer banking).
Sekring sekundernya tidak dapat mengamankan secara lengkap
melawan beban lebih dari trafo dan gangguan sekunder dengan impedansi tinggi, disebabkan sekring memerlukan waktu pemutusan yang relatif lama. Dalam susunan ini akan terjadi pemutusan total pada sekunder, jika ada bagian pelayanan sekunder yang terganggu.
2-5-3-2 Bank trafo dilengkapi sekring sekunder
Gambar 2-54. Bank trafo dilengkapi sekring sekunder pada relnya
Trafo Distribusi Sekring
sekunder
Pelayanan sekunder
Fuse Cut Out
Penyulang
Penyulan
Sekring sekunde
Trafo Distribus
Pelayanan Sekunder
Fuse Cut O t
Gambar 2-53. Bank trafo dengan ril
Sistem Distribusi Tenaga Listrik
46
2-5-3-3 Bank trafo dengan pengamanan lengkap Trafo distribusi dihubungkan ke pelayanan sekunder dengan 2 buah
"circuit breaker". Maksudnya masing-masing trafo dilengkapi 2 buah breaker yang identik. Bila arus lebih melalui sebuah dari breaker, maka breaker ini akan trip dan tidak bergantung pada breaker yang lain. Untuk suatu kegagalan trafo, maka pengaman rangkaian primer (FCO) akan terbuka (trip) bersama-sama kedua breaker sekunder.
2-6 Pelayanan Konsumen
Di dalam melayani konsumen/pemakai listrik, yang perlu diperhati kan adalah:
2-6-1 Tegangan Tegangan harus selalu di jaga konstan, terutama rugi tegangan yang
terjadi di ujung saluran. Tegangan yang tidak stabil dapat berakibat merusak alat-alat yang peka terhadap perubahan tegangan (khususnya alat-alat elektronik). Demikian juga tegangan yang terlalu rendah akan mengakibatkan alat-alat listrik tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Salah satu syarat penyambungan alat-alat listrik, yaitu tegangan sumber harus sama dengan tegangan yang dibutuhkan oleh peralatan listrik tersebut. Tegangan terlalu tinggi akan dapat merusak alat-alat listrik.
2-6-2 Frekuensi Perubahan frekuensi akan sangat dirasakan oleh pemakai listrik
yang orientasi kerjanya berkaitan/bergantung pada kestabilan frekuensi.
Hubungan dari trafo distribusi langsung ke pelayanan sekunder. Pelayanan sekunder dibagi antara trafo-trafo dengan sekring sekunder. Dalam susunan ini jika trafo mengalami gangguan, maka akan terjadi pemutusan pelayanan sekunder pada kelompok trafo yang terganggu. Sebaliknya jika ada bagian pelayanan sekunder yang terganggu, maka satu trafo pada kelompok beban tersebut terputus (trip).
Gambar 2-55. Bank trafo dengan pengamanan lengkap
Sistem Distribusi Tenaga Listrik
47
Konsumen kelompok ini biasanya adalah industri-industri yang menggunakan mesin-mesin otomatis dengan menggunakan setting waktu/frekuensi.
2-6-3 Kontinyuitas pelayanan Kelangsungan pelayanan listrik secara kontinyu merupakan
dambakan setiap pelanggan/pemakai. Pemadaman listrik dapat mengakibatkan kerugian yang besar pada industri-industri yang operasionalnya sangat bergantung kepada tenaga listrik. Oleh karenanya jika pemadaman listrik tidak dapat dihindari, misalnya karena perbaikan jaringan yang sudah direncanakan atau karena gangguan dan sebab-sebab lain, maka pelaksanaan pemadaman harus didahului dengan pemberitahuan.
2-6-4 Jenis Beban 2-6-4-1 Tarif Listrik.
Tarif listrik ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PLN, yang direkomendasikan oleh Pengumuman Menteri Pertamben dan Kepurusan Presiden. Isi Keputusan Direksi tersebut membagi beban listrik berdasar-kan jenis pemakaiannya, yaitu untuk keperluan sosial, keperluan rumah tangga, untuk keperluan usaha, untuk keperluan industri dan lain lain yang masing-masing dikelasifikasikan menurut besar kecilnya daya yang dibutuhkan dengan membedakan tarif pembayarannya. Pengelompokan tarif tersebut dapat dilihat pada tabel 2-1.
2-6-4-2 Karakteristik Beban Dari pengelompokan beban tersebut secara periodik dapat dicatat
besar-kecilnya beban setiap saat berdasarkan jenis beban pada tempat-tempat tertentu, sehingga dapat dibuat karakteristiknya .
1) Karakteristik Beban untuk Industri Besar. Pada industri besar (misalnya pengecoran baja) umumnya bekerja
selama 24 jam, sehingga perubahan beban hanya terjadi pada saat jam kerja pagi untuk keperluan kegiatan adminitrasi. Perubahan beban tersebut nilainya sangat kecil jika dibanding dengan daya total yang digunakan
P I I I I 0 6 12 18 24 jam
Gambar 2-56. Karakteristik beban untuk industri besar
Sistem Distribusi Tenaga Listrik
48
P
Penerangan jalan
untuk operasional industri. Selebihnya hampir kontinyu, selama 24 jam. Gambar 2-56 memperlihatkan karakteristik beban harian untuk industri besar yang umumnya, bekerja selama 24 jam.
2) Karakteristik Beban untuk Industri Kecil. Untuk beban harian pada industri kecil yang umumnya hanya bekerja
pada siang hari saja perbedaan pemakaian tenaga listrik antara siang dan malam hari sangat mencolok, karena pada malam hari listrik hanya untuk keperluan penerangan malam. Gambar 2-57 memper-lihatkan karakteristik beban harian untuk industri kecil yang hanya bekerja pada siang hari.
3) Karakteristik Beban Daerah Komersiil. Untuk daerah komersiil beban amat bervariasi dan beban puncak
terjadi antara pukul 17.00 sampai dengan pukul 21.00. Gambar 2-58 memperlihatkan kurve beban harian untuk daerah komersiil.
0 6 12 18 24 jam
P rata-rata
Gambar 2-58. Karakteristik beban harian untuk daerah komersiil
Gambar 2- 57. Karakteristik beban harian untuk industri kecil yang hanya bekerja pada siang hari
0 6 12 18 24 jam
P rata-rata Penerangan jalan
istirahat P
Sistem Distribusi Tenaga Listrik
49
Tabel 2-1. Penggolongan tarif tenaga listrik No. Kode Tarif Uraian Pemakaian Batas Daya 1. S-1/TR Untuk keperluan pemakai sangat kecil s/d 200VA 2. S-2/TR Untuk keperluan badan sosial kecil 250VA s/d 2.200VA 3. S-3/TR Untuk keperluan badan sosial sedang 2.201VA s/d 200kVA 4. S-4/TM Untuk keperluan badan sosial besar 201kVA ke atas 5. SS-4/TM Untuk keperluan badan sosial swasta
besar yg mengenakan tarif komersiil201kVA ke atas
6. R-1/TR Untuk keperluan rumah tangga kecil 250VA s/d 500VA 7. R-2/TR Untuk keperluan rumah tangga sedang 501VA s/d 2.200VA 8. R-3/TR Untuk keperluan rumah tangga menengah 2.201VA s/d 6.600VA9. R-4/TR Untuk keperluan rumah tangga besar 6.600 VA ke atas 10. U-1/TR Untuk keperluan usaha kecil 250VA s/d 2.200VA 11. U-2/TR Untuk keperluan usaha sedang 2.201VA s/d 200 kVA12. U-3/TM Untuk keperluan usaha menengah 201 kVA ke atas 13. U-4/TR Untuk keperluan sambungan sementara
a.l. penerangan pesta (tegangan rendah)Tergantung permintaan (sesuai kebutuhan)
14. H-1/TR Untuk keperluan perhotelan kecil 250VA s/d 99 kVA 15. H-2/TR Untuk keperluan perhotelan sedang 100 kVA s/d 200 kVA16. H-3/TM Untuk keperluan perhotelan besar 201 kVA ke atas 17. I-1/TR Untuk keperluan industri rumah tangga 450VA s/d 2.200VA 18. I-2/TR Untuk keperluan industri kecil 2.201VA s/d 13,9 kVA19. I-3/TR Untuk keperluan industri sedang 14 kVA s/d 200 kVA 20. I-4/TM Untuk keperluan industri menengah 201kVA ke atas 21. I-5/TT Untuk keperluan industri besar 30.000 kVA ke atas
22. G-1/TR Untuk keperluan gedung kantor pemerintah kecil sampai sedang
250VA s/d 200 kVA
23. G-2/TM Untuk keperluan gedung kantor pemerintah besar
201kVA ke atas 24. J/TR Untuk keperluan penerangan jalan umum Catatan : TR = Tegangan Rendah TM = Tegangan Menengah TT = Tegangan Tinggi 4) Karakteristik Beban untuk Rumah Tangga
Pemakaian beban untuk keperluan rumah tangga dalam gambar 2-59 ialah karakteristik beban untuk rumah tangga yang mana tenaga listrik sudah merupakan kebutuhan. Misalnya penggunaan kompor listrik, seterika listrik, mesin cuci, kulkas, pemanas air listrik (heater), oven listrik, AC dan lain-lain. Rumah tangga yang pemakaian listriknya seperti tersebut diatas ialah rumah tangga dengan tarif R3 dan R4.
Gambar 2-59. Karakteristik beban harian rumah tangga
P
Penerangan malam
P rata-rata
Beban puncak
Sistem Distribusi Tenaga Listrik
50
5) Karakteristik Beban untuk Penerangan Jalan
P Prata-rata
Pemakaian beban untuk keperluan penerangan jalan adalah yang
paling sederhana, karena pada umumnya tenaga listrik hanya digunakan mulai pukul 18.00 sampai dengan pukul 06.00. Gambar 2-60 memper-lihatkan kurve beban harian penerangan jalan umum.
2-6-4-3 Faktor Beban Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelayanan distribusi ialah : a. Load density = Besar daya (kepadatan beban) Luas daerah pelayanan b. Load factor = Beban rata-rata . . . . . . . . . . . <1 (faktor beban) Beban maksimum c. Demand factor = Kebutuhan beban maksimum . . . . . .<1 (faktor kebutuhan) Jumlah daya yang tersedia (kontrak) d. Diversity factor Jumlah permintaan maksimum dari (ketidak serempakan) = masing masing konsumen
Beban yang sesungguhnya dari grup(seluruh komplek) Nilai normalnya dapat mencapai 3,5 – 5 e. Coincidence factor >< Diversity factor (faktor keserempakan) Penggunaan rumus diatas ialah untuk menentukan kebutuhan penyediaan tenaga listrik pada suatu komplek perumahan.
Contoh: Suatu komplek perumahan yang baru dibangun terdiri dari 1.600
rumah, masing-masing memerlukan daya 1.300 VA. Jika faktor kebutuhan =
0 6 12 18 24 Jam
Gambar 2-60. Karakteristik beban penerangan jalan umum.
Sistem Distribusi Tenaga Listrik
51
0,6 dan faktor ketidakserempakan = 3,5, berapa KVA daya trafo yang harus disediakan untuk keperluan penyediaan tenaga listrik pada komplek tersebut Penyelesaian:
Daya maksimum = 1.800 X 1.300 X 0,6 3,5
= 356.571 ≈ 350 KVA Jika dihitung kebutuhan total = 1.600 X 1.300 VA seluruh calon pelanggan = 2.080.000 VA ≈ 2.000 KVA. Jadi daya trafo yang harus disediakan = 350 KVA ~ 400 KVA
± 1/5 X kebutuhan total calon pelanggan Jika beban terpasang = H, Faktor keserempakan = g Daya maksimum yang sesungguhnya terpakai = Pr
g = Pr. . . . . . . . . . . . . . . . . g < 1 H
Kalau jumlah rumahnya banyak, maka g < 1 dan sebaliknya untuk jumlah rumah sedikit g > 1 Pr rumah dengan elektrifikasi besar rumah dengan elektrifikasi kecil H
Tabel 2-2. Nilai g untuk bermacam-macam jenis beban No. Jenis kelompok beban g(%) 1. Komplek perumahan kecil 50-75 2. Komplek perumahan besar 40-65 3. Kantor-kantor 60-80 4. Pertokoan (Departemen store) 70-90 5. H o t e l 35-60 6. Daerah industri kecil 35-65 7. Daerah industri besar 50-80 8. Industri dengan berbagai beban a. ( 1 – 20 ) HP 70-80 b. ( 10 – 20 ) HP 60-70 c. ( 20 – 50 ) HP 55-65 d. ( 50 – 100 ) HP 50-60 e. > 100 HP 45-55
9. Untuk bengkel 10-30 10. Untuk pabrik kertas yang kontinyu 80-100
Gambar 2-61. Perbandingan nilai g untuk rumah besar dan rumah kecil
Sistem Distribusi Tenaga Listrik
52
2-7 Dasar-dasar Perencanaan Jaringan Distribusi 2-7-1 Kriteria Teknik Saluran Listrik 2-7-1-1 Batasan standar
Semua material, peralatan, perakitan dan struktur harus disesuaikan dengan kriteria teknik yang terurai di bawah ini:
2-7-1-2 Kriteria 1) Tekanan angin
Dengan mengacu kecepatan angin maksimum 80 km/jam atau 25 m/detik, temperatur minimum 26,8o C, maka diasumsikan tekanan adalah: Konduktor tunggal : 40 kg/m2 Tiang : 40 kg/m2
2) Tegangan sistem SUTM: Nominal 20kV, maksimum 24 kV, 3 kawat SUTR: Nominal 380V / 220 V, 4 kawat
3) Tingkat isolasi tegangan menengah Impulse withstand voltage : 125 kV Power frequency test voltage : 50 kV
4) Regulasi tegangan Pada sisi konsumen + 5% - 10%
5) Jatuh tegangan Pada SUTM 5%, Trafo 3%, SUTR 4% dan pada SR yang disadap dari SUTR 2%, bila disadap langsung dari trafo 12%.
6) Pentanahan titik netral pada sistem 20 kV Dengan tahanan 500 Ohm, kecuali di Madura dengan tahanan 40 Ohm.
7) Jarak bebas Batasan jarak bebas jaringan adalah: SUTM SUTR Dari permukaan tanah 6.0 m 4,0 m Menyilang jaringan 20 kV 2.0 m 2,0 m Menyilang jaringan 220 V 1.0 m 1,0 m Dengan bangunan 3.0 m 2,0 m Dengan pohon 2.0 m 0,3 m
8) Pentanahan pada SUTM: Sebagai kelengkapan dari pemasangan Arester, Trafo, LBS, Recloser, AVS dan pada ujung jaringan
9) Pentanahan pada SUTR: Dipasang pada setiap 5 gawang atau lebih, dan pada ujung jaringan. Besarnya tahanan pentanahan maksimum 5 Ohm
Sistem Distribusi Tenaga Listrik
53
2-7-1-3 Standar Pada perencanaan konstruksi standar yang dipakai sejauh tidak bertentangan adalah: 1) Standar untuk matrerial dan peralatan : SPLN (standar PLN),
IEC ( International Electronical Commision). JIS (Japanese Industrial Standard), ANSI ( American National Standard Institute) dan stadar lain yang setara.
2) Pemberian warna penandaan kawat dan kabel : merah-kuning-hitam untuk fasa, dan biru untuk netral
3) Fasa rotasi SUTM dari sisi jalan : R-S-T.
2-7-2 Perencanaan Konstruksi 2-7-2-1 Tingkat Isolasi
1) Tingkat isolasi yang dipakai adalah: Impulse withstand test voltage : 125 kV Crest Power Frequency test voltage : 50 kV rms Isolator crepage distance : 500 mm
2) Tegangan test tersebut sesuai dengan SPLN, selain itu untuk daerah kepulauan dan pantai yang diperhitungkan akan terjadi kontaminasi garam, maka dipakai isolator dengan crepage distance 500 mm.
2-7-2-2 Pelindung surja petir 1) Pelepasan arus petir secara umum dibedakan dalam pelepasan
di dalam antara awan” serta pelepasan dari awan ke tanah yang disebut sambaran ke tanah”. Kerusakan instalasi listrik disebabkan oleh sambaran ketanah dimaksud.
2) Berdasarkan map isokeraunic level, dengan asumsi 120 IKL, maka arester pelindung surja petir yang dapat diklasifikasikan:
a. Pada Out Going cable 20 kV : rating 10 kA b. Pada bagian lain : rating 5 kA
Yang dimaksud bagian lain adalah, pada Trafo, pada tiang yang terpasang kabel tanah, pada pemasangan Saklar dan tiang akhir.
2-7-2-3 Konfigurasi Saluran
Sebagaimana dipaparkan pada bab ini, konfigurasi jaringan yang paling sesuai adalah :
1) Jaringan distribusi primer: a) Saluran udara 3 kawat / 3 fasa b) Tipe Radial c) Saklar untuk mengisolasi gangguan: LBS, Recloser, untuk
Sectionalizer
Sistem Distribusi Tenaga Listrik
54
2) Jaringan distribusi sekunder: a) Saluran udara 4 kawat / 3 fasa b) Saluran udara 2 kawat / 1 fasa c) Tipe Radial d) Pengaman dengan Fuse atau Saklar Pemutus.
2-7-2-4 Konduktor dan kabel 1) Kapasitas Arus
Jenis konduktor untuk SUTM dipakai AAAC (All Aluminium Alloy Conductor), suatu campuran aluminium dengan silicium (0,4-0,7%), magnesium (0,3-0,35%) dan ferum (0,2-0,3%), mempunyai kekuatan yang lebih besar daripada aluminium murni, tetapi kapasitas arusnya lebih rendah. Untuk SUTR dipakai kabel pilin udara (twisted cable) suatu kabel dengan inti AAC berisolasi XLPE (Cross Linked polythylene), dilengkapi kawat netral AAAC sebagai penggantung, dan dipilin. Kapasitas arus adalah kemampuan daya hantar arus pada ambient temperatur 35oC, kecepatan angin 0,5 m/dt, serta daya tahan termal XLPE pada suhu 450oC. Sebagai contoh kapasitas arus tersebut dapat dilihat pada tabel 2-3.
Tabel 2-3. Daya hantar arus AAAC & XLPE cable TR
2) Pemilihan Ukuran Konduktor AAAC ukuran yang tersedia yaitu; 16, 25, 35, 50, 70, 110, 150 dan 240 mm2, sedangkan untuk Twisted Cable tersedia usuran; 3x25, 1x25; 3x35 + 1x25; 3x50 +1x35; dan 3x70 + 1x50; 2x25 + 1x25; 2x35 + 1x25; 2x50 + 1x35; mm2
3) Pemasangan Saluran Udara Konduktor harus ditarik tidak terlalu kencang dan juga tidak boleh terlalu kendor, agar konduktor tidak menderita kerusakan mekanis maupun kelelahan akibat tarikan dan ayunan, dilain pihak dicapai penghematan pemakaian konduktor. Sebagai-
Temperatur Daya hantar arus (Ampere) (oC)
AAAC XLPE cable 35 mm2 70 mm2 150 mm2 35 mm2 70mm2
90 156 244 402 129 210
75 129 199 323 106 171
60 92 138 214 74 116
Sistem Distribusi Tenaga Listrik
55
mana diketahui bahwa harga konduktor berkisar 40% dari harga perkilometer jaringan. Batasan-batasannya sebagai berikut: a) Tarikan AAAC yang diijinkan maksimum 30% dari tegangan
putus (Ultimate tensile strength). b) Tarikan Twisted cable (TC) yang diijinkan maksimum 35%
dari tegangan putus dari kawat penggantung. c) Andongan yang terjadi pada SUTM dengan jarak gawang
60-80 meter, dan pada SUTR dengan jarak gawang 35-50 meter, tidak boleh lebih dari 1 meter.
a) Andongan Menghitung andongan juga dapat dipakai rumus :
a = Wc . S2/(Pt)
dimana: a : andongan (m) Wc : berat konduktor S : Jarak gawang (m) Pt : Kuat tarik konduktor (kg)
b) Jarak gawang Penentuan jarak gawang dipengaruhi oleh:
(a) Kondisi geografis dan lingkungan (b) Jarak aman konduktor dengan tanah (c) Perhitungan tarikan dan andongan (d) Efisiensi biaya
Mengingat hal itu maka penentuan jarak gawang adalah: Daerah permukiman : jarak gawang SUTM murni, sebesar 50-60 meter, jarak gawang SUTR murni sebesar 40-50 meter. Di luar permukiman : jarak gawang SUTM murni sebesar 60-80 meter.
c) Perhitungan panjang konduktor Dengan mendasarkan penentuan dan perhitungan tersebut diatas, maka jarak gawang adalah: AAAC : panjang konduktor = jarak gawang + 1% TC : panjang konduktor = jarak gawang + 2% Perhitungan ini diperoleh dengan cara dan rumus sebagai berikut:
S’
s
a
Gambar 2-62. Andongan
Sistem Distribusi Tenaga Listrik
56
Sesuai dengan gambar 2-62, panjang konduktor S’ dapat dihitung dengan rumus:
S’ = S + (8xa2)/(3xS)
Contoh perhitungan: Bila diketahui jarak gawang S = 100 meter, konduktor AAAC 70 mm2 dari data konduktor diperoleh berat Wc = 0,208 kg/m dan UTS = 2150 kgf atau jika diambil Pt = 15% UTS = 15% x 2150 = 322,5 kgf. Andongan: a = 0,208 x 1002 / 8x322,5 = 0, 806 meter Panjang konduktor S’ = 100 + (8 x 0,8062 / 3x100) S’ = 100,0174 m, jadi S’ = (1 + 1% ) S sudah cukup
2-7-2-5 Transformator. 1) Pemilihan tipe dan kapasitas.
(a) Tipe transformador dapat dipakai: (1) Konvensional tiga fasa (2) CSP (completly self protection), tiga fasa (3) Tegangan primer 20 kV antar fasa dan 11,54 kV fasa-
netral, tegangan sekunder 380 V antara fasa dan 220 V fasa-netral.
(4) Model cantol, yaitu dicantolkan/digantungkan pada tiang SUTM.
(b) Kapasitas trafo tiga fasa. Secara umum mulai dari : 25, 50, 100, 160, 200, 250 kVA.
2) Papan bagi dan perlengkapan. (a) Papan bagi
- Pada trafo CSP fasa tiga tidak diperlukan papan bagi, SUTR langsung dihubungkan dengan terminal TR dari Trafo. Hal ini dimungkinkan karena pada CSP trafo sudah dilengkapi dengan saklar pengaman arus lebih.
- Tidak demikian halnya pada konvensional trafo, diperlukan pengaman arus lebih tegangan rendah berupa fuse/pengaman lebur, atau pemutus tegangan rendah (LVCB/low voltage circuit breaker) sehingga diperlukan almari fuse, sekaligus sebagai papan bagi untuk keluaran lebih dari satu penyulang.
- Menyesuaikan dengan penyebaran konsumen, dapat dipilih papan bagi 2 group dan 4 group.
(b) Pengaman untuk trafo konvensional - Pemisah lebur 20 kV / Fuse Cut Out, dengan rating arus
kontinyu 100A, dan kawat lebur disesuaikan dengan kapasitas trafo.
- Arrester 24 kV, 5 kA.
Sistem Distribusi Tenaga Listrik
57
- Pentanahan, terpisah antara pentanahan arrester dan pentanahan trafo.
- Pemutus daya tegangan rendah (LVCB) untuk trafo sampai dengan dengan 50 kVA.
2-7-2-6 Penentuan Konstruksi Setelah kita membahas satu persatu atas standar yang
dipakai, tentang kriteria-kriteria yang dipakai sebagai pedoman, serta berbagai hal yang berkaitan dengan material dan peralatan listrik, dan beberapa kondisi yang menjadi bahan pertimbangan dalam pemilihan/penentuan: jenis material, jenis peralatan, bahan dan ukuran dan lainnya, maka selanjutnya sudah dapat menentukan jenis konstruksi dari SUTM, SUTR dan Gardu Distribusi, dilengkapi dengan perhitungan jumlah dari material dan peralatan yang diperlukan.
Bila lokasi yang akan dibangun sudah disurvai dan dirancang rute jaringannya maka dapat dihasilkan perencanaan konstruksi yang lengkap untuk pembangunan jaringan Listrik pada lokasi yang dimaksud.
1) Jenis Konstruksi SUTM, GTT, SUTR. a) Jenis Konstruksi SUTM
Berdasarkan hal-hal yang dibahas terdahulu, terdapat konstruksi SUTM yang dipasang pada tiang disesuaikan dengan sudut belok, awal dan akhir suatu jaringan, maupun fungsi jaringan lainnya.
b) Konstruksi tiang penyangga (1) Konstruksi tiang penyangga (TM-1)
Dipakai pada jaringan lurus dan jaringan dengan sudut belok maksimum 15 derajat.
(2) Konstruksi tiang penyangga ganda (TM-2) Untuk jaringan dengan sudut belok 15-30o
15-30o TM-2 Gambar 2-64. Konstruksi tiang penyangga ganda (TM-2)
Gambar 2-63. Konstruksi tiang penyangga (TM-1)
Sistem Distribusi Tenaga Listrik
58
(3) Konstruksi tiang tarik akhir (TM-4) Sebagai tiang akhir dari suatu jaringan TM-4
(4) Konstruksi tiang tarik ganda (TM-5)
Setiap panjang jaringan lurus 500-700 meter dipasang konstruksi TM-5
TM-5
(5) Konstruksi tiang pencabangan (TM-8)
TM-8
(6) Konstruksi tiang sudut (TM-10)
Dipakai apabila sudut belok > 60o
TM-10 > 60o
Gambar 2-67. Konstruksi tiang pencabangan (TM-8)
Gambar 2-66. Konstruksi tiang tarik ganda (TM-5)
Gambar 2-65. Konstruksi tiang tarik akhir (TM-4)
Gambar 2-68. Konstruksi tiang sudut (TM-10)
Sistem Distribusi Tenaga Listrik
59
(7) Konstruksi Guy Wire Yaitu konstruksi dari topang-tarik pada tiang, untuk
menetralisir beban vertikal pada tiang. GW
(8) Konstruksi Horisontal Guy Wire Bila topang tarik tidak dapat dipasang langsung pada tiang yang bersangkutan, maka dipasang konstruksi ini. Halangan pemasangan antara lain karena tempat untuk pemasangan anchor blok tidak tersedia dekat tiang. (Gambar 2-70).
HGW
(9) Konstruksi Strut Pole
Selanjutnya, pada lokasi yang tidak memungkinkan dipasang konstruksi guy wire maupun horisontal guy wire, maka dipilih konstruksi penyangga tiang yang disebut strut pole.
SP
Gambar 2-70. Konstruksi Horisontal Guy Wire
Gambar 2-69. Konstruksi Guy Wire
Gambar 2-71. Konstruksi Strut Pole
Sistem Distribusi Tenaga Listrik
60
2). Jenis Konstruksi GTT Gardu Trafo Tiang merupakan tipe yang lebih cocok untuk perkotaan yang padat maupun pedesaan karena tidak memerlukan lahan, dapat dipasang pada pusat beban, dan dengan daya bervariasi dapat mengurangi panjang jaringan tegangan rendah
a) Konstruksi GTT tipe cantol. Pada konstruksi ini dapat dipasang trafo fasa tunggal dan fasa
tiga, yang dengan sendirinya ada perbedaan kebutuhan material/peralatannya.
b) Konstruksi GTT tipe dua tiang Untuk trafo dengan kapasitas > 50 kVA karena beratnya, tidak
mampu dipikul oleh satu tiang, maka dipasang pada dua tiang. Trafo itu biasanya jenis konvensional.
3). Jenis Konstruksi SUTR
a) Konstruksi Tiang Penyangga (TR-1) Pada jaringan tegangan rendah yang lurus atau dengan sudut belok maksimum 15 derajat, dipakai konstruksi tiang penyangga atau penggantung kabel.
b) Konstruksi Tiang Sudut (TR-2) Jaringan dengan sudut belok lebih besar dari 15 derajat sampai dengan 90 derajat, dipakai konstruksi TR-2 ini.
Sudut belok.
Gambar 2-73. GTT tipe dua tiang
Gambar 2-74. Konstruksi Tiang Penyangga (TR-1)
Gambar 2-72. Konstruksi GTT tipe cantol
Gambar 2-75. Konstruksi Tiang Sudut (TR-2)
Sistem Distribusi Tenaga Listrik
61
c) Konstruksi Tiang Awal (TR-3) Pada awal jaringan yaitu tempat dipasangnya trafo distribusi,
dipakai konstruksi TR-3.
d) Konstruksi Tiang Akhir (TR-3)
Pada ujung jaringan dipasang konstruksi TR-3
e) Konstruksi Tiang Penegang (TR-5) Secara umum pada setiap 5 gawang panjang jaringan lurus
diperlukan konstruksi penegang, yang dikenal sebagai konstruksi TR-5
f) Konstruksi Guy Wire
Seperti halnya pada SUTM, juga pada tiang awal, tiang akhir, dan tiang penegang, dari suatu SUTR diperlukan topang tarik untuk mengimbangi beban vertikal yang bekerja pada tiang.
g) Konstruksi horizontal Guy Wire
Bila penempatan anchor blok di dekat tiang tersedia, maka dapat di pasang konstruksi ini, sama halnya dengan yang dipakai pada SUTM.
h) Konstruksi Strut Pole
Dalam suatu kondisi tidak memungkinkan dipasang konstruksi guy wire maupun horizontal guy wire, dipasang suatu konstruksi penyangga yaitu konstruksi Strut Pole.
Gambar 2-76. Konstruksi Tiang Awal (TR-3)
Gambar 2-78. Konstruksi Tiang Penegang (TR-5)
Gambar 2-77. Konstruksi Tiang Ujung (TR-3)
Alat Pembatas dan Pengukur
62
BAB III ALAT PEMBATAS DAN PENGUKUR
3-1 Pembatas Satuan arus ialah Ampere, sedangkan satuan daya ialah VA. Karena
itu pembatas arus listrik menggunakan satuan Ampere. Penggunaan pembatas disebut sebagai penentuan demand (kebutuhan) pengguna. Besar arus trip pelebur atau pemutus yang digunakan sebagai pembatas maksimum ditetapkan sebesar 10% di atas arus nominal trafo yang dilindungi.
Penggunaan pembatas sebagai salah satu interface antara PLN dengan pelanggan, bila pelanggan memakai lebih pembatas akan bekerja, dan terjadi pemadaman. Dari sudut pandang pelanggan kejadian ini berarti berkurangnya keandalan suplai tenaga listrik.
Jenis-jenis alat pembatas yang paling banyak digunakan adalah jenis termis dan elektromagnet. Beberapa jenis pembatas tersebut terdiri dari pembatas satu kutub, dua kutub dan tiga kutub, seperti terlihat pada Gambar 3-1.
Beberapa contoh MCB sesuai dengan peruntukannya dapat dilihat pada
Tabel 3-1, berikut ini:
Gambar 3-1. Miniature Circuit Breaker (MCB)
Alat Pembatas dan Pengukur
63
Tabel 3-1. Jenis Pembatas dan Penggunaannya
Tabel 3-2. Contoh Data Teknik Pemutus Tenaga (MCB)
1. Pemutus Tenaga/Circuit Breaker 6 t0 63 A 1 to 40A 1 to 100A
NC45a NC45Ad NC45N
NC45H NC100H/NC125H
NC100L NC100LH
Jumlah kutub/ number of poles Tegangan isolasi pengenal / rated insulation voltage (V) Tegangan dapat ditahan impuls / impulse withstand voltage (W) Karakteristik listrik / Electrical characteristics Arus pengenal / rated current (A)Tegangan operasi pengenal / rated operational voltage (V)Ue AC 50/6OHz Kapasitas pemutusan pengenal / rated breakitzg capacitV (kA rms) SPLN108 / SLI 175 230V (IEC898) 400V IEC 947.2 Icu 240V 400V 415V 440V Ics (% of ICU)
1-2-3-4 400
6
NC45a 63
440
4,5 4,5 5 5 5 -
100
1-2-3 415
6
NC45H 40
440 - -
10 10 10 -
50
1-2-3-4 440
6
NC100L 63
440 - -
50 25 25 20 75
Jenis Pengaman MCB RCD LT SURGE
ARRESTER SAKELAR ISOLASI
Bentuk
Fungsi/ Penggunaan
Mengamankan kabel terhadap beban lebih dan hubung singkat MCB range: NC45a/aD/N/H NCIOOH/ULH
Untuk aplikasi yang hanya membutuhkan pengamanan terhadap kontak langsung dan tak langsung serta bahaya api. RCD range: EKB DPNa Vigi Modul Vigi
Mengamankan peralatan listrik dan elektronik terhadap tegangan transien yang disebabkan oleh petir dan industri, seperti penyalaan motor besar. LT terdiri dari 2 jenis LTM dan LTD dengan Imax., LTM 40kA LTD 6,5 kA
Pembuka dan penutup sirkuit saat berbeban
Alat Pembatas dan Pengukur
64
2. Kombinasi Pemutus Tenaga mini/gawai arus bocor/ combined mcb/rcd 6 t0 32 A 1 to 100A
DPNa Vigi Vigi module
Jumlah kutub / number of poles Karakteristik listrik / electrical characteristics Arus pengenal / rated current (A) In 401C Tegangan operasi pengenal / rated operational voltage (V) Ue AC Kapasitas pemultusan pengenal / rated breaking capacity (kA nns) SPLN 108/SLI 175 (IEC 898) 230V IEC 947.2 230V Unit trip (tak dapat disetel) / trip units (non adjustable) Jenis curva / curve type C (Im = 5 to In) Pengamanan arus bocor / earth leakage protection 30 mA to 300 mA Jenis selektif I Selective type Lengkapan instalasi / Installation accesson I es Gawal penguncian / padlocking device
1 + N
32(at 301C) 230V(5016OHz)
4,5 6
- - -
2,3,4
1A to 100A 240/415V
mcb mcb
- - -
3. Pemutus Tenaga arus bocor/ earth leakage breaker (ELCB) 25 to 100A
ID/EKB
Jumlah kutub I number of poles Tegangan operasi /operational voltage Arus pengenal / rated current Sensitifitas / sensitivities Tunda waktu / time delay Alat bantu fistrik / electrical auxiliary Saklar bantu / auxiliary switch (OFS1OF) Pemutus tegangan jatuh/ under voltage trip (MN) Pemutus shunt / shunt trip (MX) Lengkapan accessories Tutup terminal / sealable terminal shield Pembatas antar kutub / interpole barrier Gawai penguncian / padlocking device
2,4 240/415 Vac 25 to 100 A 30 to 300 mA - (300 mA only) - - - - - -
Alat Pembatas dan Pengukur
65
3-2 Pemasangan, pengoperasian dan pemeliharaan Cara pemasangan pembatas type MCB ini sangatlah mudah, karena
konstruksi pada bagian bawah MCB sudah dilengkapi dengan ril, sehingga begitu ril dipasang MCB tinggal memasukkan dari arah samping dan didorong sesuai dengan posisi yang diinginkan.
Demikian pula dalam pengoperasian, tinggal mendorong ke atas untuk posisi ON, dan menekan ke bawah untuk posisi OFF.
Dalam pemeliharaan, jika hal ini terkait dengan PLN maka setting/peneraan/mengganti baru menjadi tanggung jawab PLN, sedang pada industri umumnya diganti baru. Hal ini berkaitan dengan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh pengaman, diantaranya peka, cepat reaksi, andal, dan harganya tidak terlalu mahal.
3-3 Alat Ukur Energi Arus Bolak-balik
3-3-1 Prinsip-prinsip Kerja Dalam alat ukur energi, kumparan-kumparan arus dan tegangan
merupakan suatu belitan pada dua buah magnet seperti tampak pada Gambar 3-2. Kumparan arus akan membangkitkan fluks magnet, (Φ1, dengan nilai berbanding Iurus terhadap besar arus. Sementara kumparan tegangan akan membangkitkan fluks magnet, (Φv).
Perputaran dari piringan aluminium terjadi karena interaksi dari kedua medan magnet ini. Fluks magnetik akan membangkitkan arus Eddy pada piringan yang akan menghasilkan gaya yang melawan arah putaran piringan. Gaya yang dihasilkan berbanding lurus terhadap sudut fasa antara fluks-fluks kumparan tegangan dan kumparan arus, gaya maksimum akan terjadi jika sudut fasanya 90O. Gaya ini sebanding dengan daya aktif V I
cos θ, yang sama dengan kecepatan putaran piringan. Jumlah putaran dalam waktu tertentu akan memberikan peng ukuran dari energi yang digunakan karena energi = daya x waktu.
Batang besi untuk piringan putar dilekatkan pada peng-hitung putaran melalui sistem gigi yang tepat yang dikalibrasikan untuk mengukur kilowatt hours (kWh) yang merupakan satuan energi listrik.
Gambar 3-2. Konstruksi KWH meter
Alat Pembatas dan Pengukur
66
3-3-2 Tang Ampere Alat ukur tang ampere atau dikenal juga dengan sebutan Ampere
meter jepit bekerja dengan prinsip, yang sama dengan inti primer sebuah transformator arus seperti tampak pada Gambar 3-3. Dengan alat ukur tang ampere ini pengukuran arus dapat dilakukan tanpa memutuskan suplai listrik terlebih dahulu. Konstruksi dari alat ukur tang ampere ini diperlihatkan pada
Gambar 3-3.
3-3-3 Register Satu alat mengintegrasikan dan memperlihatkan jumlah perputaran dari kepingan disebut register. Register dibuat sebagai petunjuk diperlihatkan dalam Gambar 3-4a, yang mempergunakan penunjuk untuk memperlihatkan jumlah perputaran. Di samping itu terdapat pula register cydometris yang diperlihatkan pada Gambar 3-4b yang
mempergunakan roda-roda angka.
3-3-4 Transformator untuk Alat-alat Pengukuran Dalam keadaan arus searah, maka untuk memperbesar daerah
pengukuran suatu tahanan shunt atau seri dipergunakan. Untuk kepentingan yang sama maka dalam keadaan pemakaian pada arus bolak balik, suatu transformer khusus yang dikenal sebagai transformator alat-alat pengukuran dipergunakan. Dalam prinsipnya suatu transformator alat pengukur adalah identik dengan transformator daya, akan tetapi dalam transformator alat-alat
Gambar 3-4. Bentuk-bentuk penunjukan (register)
(a)-1 (a)-2 (b)
Gambar 3-3. Tang Ampere
Alat Pembatas dan Pengukur
67
pengukuran yang dipentingkan bukanlah kerugian-kerugian daya, akan tetapi kesalahan-kesalahannya. Suatu keadaan yang menguntungkan dalam penggunaan transformator alat-alat pengukuran adalah, bahwa alat pengukur akan mungkin diisolasikan dari pada jaringan-jaringan utama. Transformator untuk alat-alat pengukuran dapat berupa transformator untuk arus dan tegangan. Transformator untuk arus dikenal sebagai transformator arus (TA), dan transformator untuk tegangan dikenal sebagai transformator tegangan (TP). Penggunaan transformator-transformator tersebut pada umumnya dilakukan pada frekuensi-frekuensi komersiil akan tetapi kadang-kadang pula dipergunakan pada frekuensi audio.
3-3-4-1 Prinsip-prinsip Kerja Dalam Gambar 3-5 diperlihatkan transformator yang mempunyai lilitan
primer N1, dan lilitan sekunder sebanyak N2, yang dihubungkan dengan beban Z pada lilitan-lilitan sekundemya. Dengan lilitan primernya dihubungkan dengan sumber daya arus bolak balik seperti diperlihatkan pada Gambar 3-5(a), rasio dari lilitan-lilitan adalah n = N1/N2. Misal tegangan primer arus V1, dan tegangan sekunder V2, arus primer I1, dan arus sekunder I2.
Mengingat suatu transformator yang ideal akan memenuhi persamaan-persamaan:
V1 = - nV2 (3.1)
I1 = - 1 I2 (3.2) n maka persamaan antara tegangan primer dan tegangan sekunder, serta antara arus primer dan arus sekunder hanya ditentukan oleh rasio dari lilitan-lilitan. Akan tetapi dalam prakteknya, sebagian dari arus I, dipakai untuk membangkitkan fluksi magnitis di dalam kumparan besi. Nyatakanlah bagian ini sebagai Io, maka:
n l1 = - I2 + Io. (3.3)
Kemudian arus primer I1, membangkitkan fluksi magnitis Φ1, yang hanya memotong kumparan-kumparan primer yang mengakibatkan adanya satu reaktansi X1, yang dihubungkan di dalam seri dengan kumparan-kumparan primer. Akan tetapi disamping reaktansi ini kumparan primer masih
Gambar 3-5. Rangkaian Prinsip Kerja Transformator
Alat Pembatas dan Pengukur
68
mempunyai tahanan rx. Jadi dengan kombinasi r1, dan x1, kumparan primer dapat dianggap sebagai kumparan ideal yang dihubungkan secara seri dengan suatu impedansi (r1 + jx1). Impedansi ini akan disebut impedansi kebocoran primer; kumparan sekunder dapat pula dianggap sebagai kumparan ideal yang dihubungkan secara seri dengan impedansi bocor (r1 + jX2). Jadi cara kerja dari transformator ini dapat dinyatakan dengan Gambar 3-5(b). Oleh sebab itu maka persamaan-persamaan diatas tidak berlaku. Arus IO disebut arus magnitisasi, dan YO disebut aknitansi magnitisasi. Rasio (3.4)
dimana V1n dan V2n. adalah harga-harga nominal dari tegangan- tegangan primer dan sekunder dari transformator, dan rasio (3.5) dimana I1n dan I2n adalah harga-harga nominal dari arus-arus primer dan sekunder, disebut rasio-rasio transformator nominal yaitu untuk masing-masing arus dan tegangan. Bila, rasio transformator yang sebenarnya, dinyatakan dengan K maka untuk transformator tegangan,
(3.6) dan dengan demikian, maka kesalahan transformasi atau juga disebut kesalahan ratio dapat dinyatakan sebagai (3.7) atau
(3.8)
Demikian pula dalam keadaan yang sama maka kesalahan ratio
untuk transformator arus dapat dinyatakan sebagai
(3.9)
nn
n KVV
=2
1
nn
n KII
=2
1
2
1
VVK =
1
12
VVVK
KKK nn −=
−=ε
%1001
12 xV
VVK n −=ε
%1001
12 xI
IIK n −=ε
Alat Pembatas dan Pengukur
69
Dalam pengukuran daya dengan mempergunakan transformator-
transformator pengukuran, maka terdapat suatu masalah yang disebabkan oleh persamaan-persamaan fasa antara (Φ1 dan Φ2, lagi pula berkaitan dengan I1 dan I2. Bila – V2 atau –I2, yang didapatkan dengan memutarkan fasor-fasor dari kebesaran sekunder dengan 180O mempunyai fasa di depan terhadap V1 atau I1, maka secara konvensionil disebutkan, bahwa perbedaan fasa dari transformator adalah positif. Besar perbedaan fasa ini dinyatakan dalam menit. Impedansi beban pada transformator ini disebut beban, dan besarnya dinyatakan dalam daya nyata atau VA, sesuai dengan harga-harga nominal dari kebesaran- kebesaran sekunder. Sebagai contoh, bila beban dari suatu transformator adalah 100 VA, dan tegangan nominal dari transformator adalah 110 V, maka Zb = 1102/100 = 121 Ω. Demikian pula bila beban dari suatu transformator arus adalah 20 VA dan arus nominal sekunder adalah 5 A, maka Zb = 20/52 = 0,8 Ω. Sebagai catatan, maka komponen reaktif dari beban biasanya, dinyatakan dengan faktor kerjanya, sebagai contoh misalnya beban 20 VA, faktor kerja 0,8.
3-3-4-2 Transformator-transformator Arus Seperti diperlihatkan dalam Gambar 3-6, transformator arus
dipergunakan dengan dihubungkannya dalam seri kumparan primernya dengan beban, kumparan sekundernya dihubungkan dengan sirkit arus dari alat pengukur amper atau alat pengukur watt. Dalam transformator arus, kesalahan terjadi terutama disebabkan oleh adanya magnitisasi, yang didapat dari sebagian arus primer.
Arus magnitisasi tersebut yang akan membangkitkan fluksi di dalam
inti magnitnya. Untuk membuat kesalahan ini kecil maka inti besi dibuat dari material yang mempunyai permeabilitas yang tinggi dan jumlah lilitan diperbanyak. Disamping ini, maka jumlah lilitan dari kumparan sekunder dalam banyak hal dikurangi dengan I % bila dibandingkan dengan harga yang ditentukan oleh transformator nominalnya. Cara-cara untuk membuat lilitan dari transformator arus adalah sebagai berikut. Terdapat pada
Gambar 3-6. Transformator Arus Gambar 3-7. Jenis-jenis Trafo Arus
Alat Pembatas dan Pengukur
70
dasarnya dua cara pokok yaitu yang menghasilkan transformator arus dari type lilitan dan dari type tusukan. Dalam type lilitan maka kedua kumparan primer dan sekunder dililitkan melalui satu inti besi sedangkan dalam type tusukan, maka sebagai kumparan primer dipergunakan satu konduktor tunggal yang ditusukkan melalui jendela yang dibentuk dari inti-inti besinya.
Disamping tipe lilitan dan tusukan tersebut, masih terdapat apa yang dikenal sebagai tipe jendela dimana lilitan primernya tidak diberikan akan tetapi pemakai dapat membentuknya sendiri pada saat penggunaannya dengan memberikan sejumlah lilitan yang diperlukan pada sisi primemya. Tipe lilitan dipergunakan pada umumnya bila harga nominal dari arus primer adalah di bawah 1.000 A. Sedangkan tipe-tipe lainnya dipergunakan pada arus-arus primer yang mempunyai harga nominal lebih tinggi.
Cara-cara menempatkan isolasi adalah sebagai berikut. Pada umumnya terdapat tiga isolasi, yaitu isolasi kering, yang hanya mempergunakan isolasi udara, di samping isolasi-isolasi yang terdapat pada pengantar masing-masing, yang biasanya mempergunakan pengantar-pengantar khusus diperuntukkan lilitan-lilitan transformator; isolasi kering padat dimana lilitan-lilitan dimasukkan ke dalam zat yang pada mulanya adalah cair, akan tetapi dalam keadaan akhimya membeku dan dengan demikian maka seluruh lilitan-lilitan tersebut terdapat di dalam suatu rumah yang dibentuk oleh material isolasi yang telah membeku tersebut. Isolasi minyak dimana kumparan-kumparan dimasukkan di dalam suatu bejana yang berisi minyak khusus untuk isolasi. Seleksi dari pada cara-cara isolasi tersebut tergantung kepada penggunaan dari pada transformator, arus atau tegangan, pula dari pada jala-jala dimana transformator, arus tersebut dipergunakan.
Gambar 3-7 memperlihatkan transformator arus yang diper- gunakan dalam jala-jala tegangan tinggi. Transformator tersebut ditempatkan pada suatu isolator tegak yang tinggi. Bila kumparan sekunder dari transformator arus dibuka sedangkan arus primemya mengalir maka tidak ada arus sekunder yang mengalir, dan arus primer secara menyeluruh dipakai untuk magnitisasi. Hasilnya adalah kerugian-kerugian besi akan menaik secara berlebihan dan akan memungkinkan menyebabkan pemanasan yang sangat besar atau tegangan yang diinduksikan pada kumparan sekunder akan mungkin menaik secara berlebihan sehingga menyebabkan isolasi-isolasinya pecah dan tidak mungkin menahan tegangan yang demikian besamya. Jadi pada penggunaan transformator arus tidak diperkenankan untuk membuka kumparan-kumparan sekundemya bila arus primernya mengalir. Sebagai contoh, bila, dalam penggunaan diperlukan untuk mengganti sesuatu alat pengukur pada jaringan-jaringan sekunder dari transformator arus, adalah suatu keharusan untuk menghubung pendek kumparan-kumparan arus terlebih dahulu.
Alat Pembatas dan Pengukur
71
3-3-4-3 Transformator Tegangan Seperti diperlihatkan pada Gambar 3-8 transformator tegangan dipergunakan dengan menghubungkan kumparan-kumparan primernya
secara paralel dengan beban, dan kumparan sekundernya dihubungkan dengan sirkit tegangan dari pengukur Volt atau pengukur Watt. Dengan cara demikian, maka kumparan primer dan sekunder diisolasikan secara cukup dari satu dan lainnya, sehingga tegangan tinggi bisa ditransformasikan ketegangan rendah, untuk keperluan pengukuran dengan aman. Dalam kebanyakan penggunaan maka tegangan primer adalah di bawah
300 kV. Pada transformator tegangan, suatu kesalahan negatif sering terjadi, yang disebabkan oleh adanya kerugian tegangan pada kumparan-kumparan sekundernya dan arus magnitisasinya. Untuk mengkompensasikan kesalahan ini, maka jumlah lilitan pada tegangan primer sedikit dikurangi dari pada rasio nominal dari lilitan-lilitannya. Cara--cara isolasi sama untuk transformator arus pada Gambar 3-9 memperlihatkan transformator tegangan yang biasanya dipergunakan.
3-3-4-4 Pembagi Tegangan Kapasitip Penggunaan dari transformator tegangan yang dijelaskan pada paragraf yang lalu terbatas dalam penggunaannya kira-kira pada 300 kV. Untuk pengukuran pada tegangan yang lebih tinggi, pembagi tegangan kapasitip seperti diperlihatkan pada Gambar 3-10 lebih menguntungkan terutama karena masalah-masalah isolasinya lebih mudah dipecahkan.
Gambar 3-8. Trafo Tegangan
Gambar 3-9. Jenis-jenis trafo tegangan
Alat Pembatas dan Pengukur
72
Akan tetapi karena pengambilan langsung dari arus melalui terminal-terminal pengukurannya akan mungkin menyebabkan kesalahan yang besar, suatu induktansi ditempatkan seperti diperlihatkan pada Gambar 3-10(b). Dengan cara ini, dan karena adanya resonansi maka ratio dari V1, ke V2 hanya
tergantung kepada C1 dan C2 dan tidak dipengaruhi oleh beban. Alat pembagi tegangan, tersebut disebut sebagai pembagi tegangan kapasitip. Dengan melihat pada Gbr. 3-10(b),
(3.10)
(3.11) Dengan demikian (3.12)
Bila konstanta-konstanta di atas dipilih sehingga memenuhi hubungan (3.13)
maka persamaan berikut ini didapatkan (3.14)
b
b
ZLjZ
YCjY
VV
++
+=
ωω /1/1/1
1
2
bZLjCjY
++=
ωω 1
bZCjCCL
CCC
VV
1
212
1
21
1
2 )(1ω
ω +−+
+=
1( 212 =+CCLω
1
21
1
2
CCC
VV +
=
Gambar 3-10. Alat Pembagi Tegangan Kapasitor
Alat Pembatas dan Pengukur
73
Jadi V1/V2, tidak tergantung dari beban, yaitu Zb. Akan tetapi karena persamaan 4.54 tergantung dari frekuensi maka V1/V2 akan mempunyai karakteristik frekuensi.
3-3-4-5 Pengukuran arus pada jaringan Bila arus yang melalui suatu jaringan akan diukur sedangkan tidak
memungkinkan memotong jaringan tersebut untuk menghubungkan alat pengukur ampere, atau melalui suatu transformator arus, maka penggunaan dari alat ukur ampere jaringan, akan merupakan pemecahan yang sangat baik. Seperti diperlihatkan dalam Gambar 3-11(a), alat ukur ampere jaringan dibuat dengan kumparan besi dalam bentuk seperti garpu yang mempunyai banyak lilitan, dan membentuk kumparan sekunder, dan satu pengantar sebagai kumparan primer dari satu lilitan, yang terdiri dari pengantar dimana arus yang akan diukur mengalir. Bila pengantar ditempatkan di antara inti besi seperti diperlihatkan dalam gambar, arus sekunder yang berbanding lurus dengan arus yang akan diukur didapat pada penunjukan dari alat pengukur ampere. Akan tetapi dengan cara pengukuran ini dimana jalan magnitis tidak menutup, maka kesalahan-kesalahan yang tergantung dari
Gambar 3-11. Kombinasi-kombinasi transformator pengukur dan Wattmeter
Gambar 3-12. Pengukuran arus pada kawat penghantar
Alat Pembatas dan Pengukur
74
posisi pemasukan dari pengantar ke dalam inti, ditambah pula kesalahan bentuk gelombang dan frekuensi adalah besar. Untuk mengurangi kesalahan-kesalahan tersebut maka alat ukur ampere yang digantungkan seperti diperlihatkan dalam Gambar 3-12(b) lebih baik dipergunakan. Dalam alat ukur ini jalan garis-garis magnit hanya terbuka pada saat memasukan pengantar ke dalam inti besi, sedangkan garis-garis magnit tersebut menutup pada saat pengukuran dijalankan.
3-4 Jenis-jenis kWH Meter Berdasarkan kebutuhan pelayanan kWh meter dapat dibedakan
menjadi 2 Jenis, yaitu:
3-4-1 kWh meter 1 phasa kWh meter jenis ini sering kita jumpai dan lebih dikenal karena kWh
ini banyak terpasang di rumah-rumah. kWh meter 1 phasa mempunyai kemampuan tegangan 127/220 V dan 220/380 V, 5(20) A, 50 Hz dan digunakan untuk daya sampai 4400 VA. Di bawah adalah gambar pengawatan kWh meter I phasa 2 kawat.
3-4-2 kWh meter 3 phasa kWh meter ini banyak digunakan di industri-industri ataupun rumah mewah. kWh meter 3 phasa dapat dibedakan lagi menjadi 2 macam menurut diagram pengawatannya (jumlah kawat), yaitu:
3-4-2-1 kWh meter 3 phasa 4 kawat kWh meter 3 phasa 4 kawat adalah yang paling umum digunakan
atau terpasang di industri-industri. Hal ini disebabkan dalam pengawatan dan pemasangannya lebih mudah untuk dikerjakan. Oleh karena tegangannya 3 phasa, maka kWh meter ini mempunyai 3 kumparan arus, 3 kumparan tegangan, dan 3 kumparan pengatur cos ϕ. kWh meter ini dilengkapi 2 register (angka pencatat energi), yaitu yang satu untuk beban maksimum (WBP) sedangkan yang lain untuk beban normal (LWBP). Untuk diketahui, beban puncak biasanya diberlakukan mulai pukul 18.00 - 22.00. KWh meter ini juga dilengkapi 10 terminal untuk penyambungan ke beban
Gambar 3-13. Diagram Pengawatan kWH Meter 1 phasa 2 kawat.
Alat Pembatas dan Pengukur
75
dan 2 terminal untuk penyambungan ke timer (sebagal pemindah register). Gambar rangkaian dari kWH meter 3 phasa 4 kawat dapat dilihat pada gambar 3-14.
3-4-2-2 kWh meter 3 phasa 3 kawat Sekarang ini kWh meter 3 phasa 3 kawat sedang direkomen dasikan pemakaian/ pemasangan nya pada industri-industri. Hal ini dikarenakan konstruksinya dan pengawatannya sederhana, sehingga dalam, pemasangannya lebih efisien dan ekonomis (untuk beban seimbang tanpa netral (A).
Perbedaan kWh meter 3 phasa 3 kawat dengan kWh meter 3 phasa 4 kawat adalah, kWh meter 3 phasa 3 kawat ini hanya mempunyai 2 kumparan tegangan, 2 kumparan arus, 2 pengatur cos ϕ serta, 7 terminal beban. Sama halnya dengan kWh meter 3 phasa 4 kawat, kWh meter 3 phasa 3 kawat ini uga dilengkapi dengan 2 register dan 2 terminal timer. Pada kWh meter ini tidak terdapat kawat nol (netral), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3-15, di bawah ini.
Ketiga jenis kWh meter di atas merupakan alat ukur yang cara bekerjanya secara analog. Tetapi dewasa ini telah diciptakan kWh meter elektromik (digital) dan sampai saat ini banyak yang sudah menggunakannya, khususnya untuk pelanggan-pelanggan besar atau
industri yang daya terpasangnya di atas 200 kVA.
Dengan memasang kWh meter elektronik ini dapat memudahkan kinerja PLN dalam mengecek pemakaian energi listrik para pelanggan. Hal ini dikarenakan kWh meter elektronik ini dihubungkan ke sebuah modem, sehingga dapat diakses secara on-line dengan komputer. Dari pernasangan kWh meter elektronik dapat diketahui arus tiap phasa, tegangan tiap phasa, faktor kerja (cos ϕ) tiap phasa, frekuensi dan daya.
Gambar 3-15. Diagram Pengawatan
kWH Meter 3 phasa 3 kawat.
Gambar 3-14. Diagram Pengawatan kWH Meter 3 phasa 4 kawat.
Alat Pembatas dan Pengukur
76
kWh meter elektronik ini dilengkapi dengan baterai 9 Volt dan pada modem terdapat kartu handphone yang digunakan untuk pernanggilan (akses). Gambar 3-16 menunjukkan bentuk dari kWh meter elektronik tersebut.
3-4-3 Meter Standar Suatu kWh meter yang akan dipasang pada pelanggan sebelumnya harus sudah dilakukan peneraan terhadap kesalahan- kesalahan (error) kWh meter sesuai dengan batas dan kelasnya. Peneraan ini menggunakan suatu alat yang disebut meter standar. Meter standar adalah suatu alat ukur energi yang dibuat khusus dengan ketelitian tertentu. Meter standar ini digunakan sebagai alat pembanding kesalahan-kesalahan (error) pada kWh meter. Karena fungsinya sebagai pembanding, maka, meter standar ini memiliki akurasi kesalahan sampai dengan 0,5 % dan spesifikasinya, adalah 127 V, 5 A dan 500 rev/kWh.
Meter standar ini dihubungkan ke alat penghubung yang dinamakan meja tera. Jadi dalam pelaksanaan pengujian, meter standar tidak langsung dihubungkan ke kWh meter yang diuji melainkan melalui meja tera lebih dahulu. Suatu pengujian kWh meter dapat dilakukan sampai 3-20 buah kWh meter secara bersamaan. Gambar 3-17 memperlihatkan bentuk meter standar.
3-4-4 Sistem Pengamanan kWh Meter Seperti yang telah diketahui bahwa PLN sering mengalami kerugian-kerugian, ini tidak hanya pada material namun juga energi listrik
Gambar 3-16. Bentuk kWH Meter Elektronik
Alat Pembatas dan Pengukur
77
yang secara langsung pada kerugian finansial. Kerugian-kerugian PLN sering disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran energi listrik yang dilakukan para pelanggan. Banyak cara yang dilakukan pelanggan dalam melakukan pelanggaran energi listrik. Salah satunya adalah dengan membuka/merusak segel kWh meter. PLN sebagai perusahaan listrik negara dalam hal ini sudah mengantisipasi tindakan-tindakan pencurian tersebut dengan memberikan segel-segel di bagian alat ukur, antara lain:
- Segel kWh meter - Segel terminal - Segel terminal kWh - Segel clock (jam) - Segel kVARh meter - Segel jendela APP - Segel terminal kVArh - Segel pintu APP - Segel kVA max
Seiring dengan kemajuan jaman yang serba canggih ini, PLN juga memanfaatkannya untuk keperluan sistem pengamanan kWh meter. Sistem pengamanan ini berupa kunci elektronik (cyber key). Dinamakan kunci elektronik karena kunci ini dilengkapi bateri 9 volt, validator dan didalamnya menggunakan software. Fungsi validitor adalah sebagai alat penghubung dari kunci elektronik ke komputer yang digunakan untuk memasukkan (download) data. Kunci elektronik ini mempunyai nomor seri atau alamat sehingga dalam memasukkan data tidak terjadi kesalahan. Seperti pada umumnya, kunci elektronik terdiri dari 2 bagian yaitu kunci dan gembok. Pemasangan kunci elektronik ialah khusus untuk pelanggan yang dayanya di atas 200 kVA (industri-industri) dan dipasang pada pintu APP (Alat Pembatas dan Pengukur) dari suatu gardu listrik.
Gambar 3-17. Bentuk meter standar
Alat Pembatas dan Pengukur
78
Cara penggunaan kunci elektronik ialah apabila petugas PLN akan mengadakan pengecekan kWh meter di suatu industri, maka pemegang kunci memberikan kunci elektronik yang sebelumnya telah dimasukkan datanya ke komputer. Kemudian pada pukul 21.00 dengan sendirinya kunci elektronik akan mengirimkan laporannya ke komputer, sehingga di komputer dapat diketahui jam berapa gardu dibuka.
3-4-5 Peneraan kWh Meter 3-4-5-1 Peneraan kWh meter 3 phasa 4 kawat dengan metode Meter
Standard kWh meter yang akan dipasang (di pelanggan), terlebih dahulu harus
melalui suatu proses yang disebut peneraan. Tujuan dari peneraan adalah agar kesalahan penunjukkan kWh meter yang terjadi berada dalam batas-batas yang diizinkan. Peneraan kWh meter dapat dilakukan antara lain dengan melalui Meter Standard, Watt Meter dan Stopwatch. Jika kita menera kWH meter dengan Meter Standard, peneraan dengan cara ini adalah membandingkan energi yang ditunjukkan kWh meter yang ditera dengan energi yang ditunjukkan di Meter Standard. Dan kWh meter yang kita tera adalah kWh meter 3 phasa 4 kawat karena semua kWh meter baik 1 phasa 2 kawat dan 3 phasa 3 kawat prinsipnya sama dalam melakukan peneraan. Langkah-langkah peneraan kWh meter adalah sebagai berikut: a. Pemeriksaan visual dan mekanis
Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk melihat ada tidaknya cacat pada meter. Kemudian tutup meter dilepas dan memeriksa bagian- bagian meter, antara lain:
1) Kotak meter 2) Rangkaian register 3) Kekencangan sekrup
Gambar 3-18. Bentuk Kunci Elektronik
Alat Pembatas dan Pengukur
79
4) Kebersihan bagian dalam meter, terutama sela pada bagian magnet peredaman
5) Dan bagian lain yang dianggap perlu
Setelah pemeriksaan di atas selesai, langkah selanjutnya yaitu kumparan arus dan kumparan tegangan kWh meter dihubungkan ke meja tera/Meter Standard. Kumparan arus dibubung seri sedangkan kumparan tegangan dihubung paralel.
b. Pemanasan awal Sebelum peneraan dilaksanakan, dilakukan pemanasan awal terlebih
dahulu. Langkah ini dimaksudkan untuk memberikan pemanasan sesuai dengan temperatur kerja kWh meter, guna memperoleh kestabilan hingga kesalahan akibat perbedaan suhu menjadi minimum. Pemanasan ini dilakukan selarna 30 sampai 60 menit dengan memberikan arus dan tegangan nominal pada cos ϕ = 1.
c. Pengujian register Pengujian register ini dilakukan pada waktu pemanasan awal. Jadi disamping menjalankan kWh meter juga dilihat penunjukan register. Maksud dari pengujian ini adalah untuk membuktikan kebenaran dari konstanta meter yang ditera. Jika dalam pengujian ini terjadi kesalaban menghubungkan kabel ke kumparan arus maupun tegangan, maka register tidak berputar. Cara pengujian konstanta (c) meter dengan satuan jumlah putaran per kWh meter ada 2 cara, yaitu: 1) Menghitung jumlah putaran piringan dan selisih penunjukkan
register Dengan cara ini, konstanta (c) yang diperoleh sebagai berikut: (3.15)
dimana: c = konstanta n = putaran piringan A = posisi awal register dalam kWh B = posisi akhlr register dalam kWh
(SPLN. 60-3: 1992)
2) Menghitung selisih penunjukkan register dalam membandingkan dengan energi pada Meter Standard Dengan cara ini, pertama-tama kita harus mengetahui selisih penunjukkan register, kemudian membandingkan energi yang ditunjukkan register. Jadi selisih register harus sama atau mendekati energi (E) yang dirumuskan:
−=
kWhputaran
ABnc
Alat Pembatas dan Pengukur
80
E = p x t (3.16)
dimana:
E = Energi (kWh) p = Penunjukkan meter (watt) t = Waktu Oarn) (SPLN. 60-3: 1992)
Kelemahan cara ini adalah bahwa suplai harus stabil.
3) Pemeriksaan kopel penahan (perputaran tanpa beban) Pemeriksaan ini dimaksud untuk mengetahui bahwa piringan kWh
meter bila arus = 0, maka piringan kWh meter tidak boleh berputar. Cara pemeriksaan ini adalah kumparan tegangan diberi tegangan antara 80% - -110% tegangan nominal dan kumparan arus dalam keadaan tanpa arus (tidak diberi arus).
4) Pemeriksaan arus mula Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk memeriksa nilai arus
terkecil suatu kWh meter yang sanggup memutar piringan terus mencrus. Langkah ini dilakukan dengan cara:
- Kumparan tegangan diberi tegangan nominal - Kumparan arus diberi arus sesuai dengan tabel di bawah ini dengan faktor daya 1
Tabel 3-3. Arus Mula
Meter Arus Mula (%) Id = Meter Kelas 0,5 1,0 2,0
Meter tarif tunggal tanpa penahan putaran balik 0,3 0,4 0,5
Meter lainnya 0,4 0,4 0,5
5) Pemeriksaan keseimbangan kopel Tujuan pengujian Ini adalah untuk menghindarkan meter dari
kesalahan ukur yang melampaui batas, bila meter dibebani beban tak seimbang. Keseimbangan kopel, tercapai bila piringan tidak berputar.
Keseimbangan ini diperiksa dengan memberikan tegangan nominal pada dua kumparan tegangan secara paralel dan arus dasar pada cos ϕ = 1 pada dua kumparan arus yang dihubung seri tetapi dengan polaritas yang berlawanan. Sehingga diperoleh besar kopel putar yang sama besar tiap--tiap phasa.
6) Pengujian karakteristik beban Dari langkah-langkah peneraan di atas, pengujian karakteristik beban
merupakan langkah yang paling utama. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kesalahan ukur suatu meter untuk berbagai nilai arus dengan batas kesalahan yang diizinkan.
Alat Pembatas dan Pengukur
81
Pengujian dilakukan dengan cara memberikan tegangan nominal dan memberikan arus sesuai dengan titik tera. Pengujian karakteristik beban dilakukan pada:
1) Titik Tera 1, yaitu dengan memberikan arus pada kumparan arus sebesar 1001% Id (Arus dasar meter) dengan faktor daya (untuk tera beban penuh (FL))
2) Titik Tera 2, yaitu dengan memberikan arus pada kumparan arus sebesar 100% Id (Arus dasar meter) dengan faktor daya 0,5 (untuk tera faktor daya (PF))
3) Titik Tera 3, yaitu dengan memberikan arus pada kumparan arus sebesar 5% Id (Arus dasar meter) dengan faktor daya 1 ( untuk tera beban rendah (LL)
Jika dalam pengujian di atas kesalahannya melebihi batas yang diizinkan, maka dilakukan penyetelan, antara lain:
1) Pada Titik Tera 1, penyetelan dilakukan dengan mengatur shunt magnetis rem magnet, yang pada kWh meter ditandai dengan tulisan FL
2) Pada Titik Tera 2, penyetelan dilakukan dengan mengubah kedudukan alat penyetel faktor daya.
2) Pada Titik Tera 3, penyetelan dilakukan pada alat penyetelan Beban rendah, yang pada kWh meter ditandai dengan tulisan LL
Di bawah ini adalah tabel batas kesalahan presentase yang dlizinkan.
Tabel 3-4. Batas Kesalahan Presentase yang Diijinkan
Arus Dasar (% Id)
Faktor Daya
(Cos ϕ )
Batas Kesalahan
kWh Kelas 2
Batas Kesalahan
kWh Kelas 1
Batas Kesalahan
kWh Kelas 0,5 100 100
5
1,0 0,5 1,0
± 2,0 %± 2,0 % ± 2,5 %
± 1,0 %± 1,0 % ± 1,5 %
± 0,5 % ± 0,8 % ± 1,0 %
Rumus untuk mengetahui batas kesalahan suatu alat ukur adalah:
(3.17)
dimana: S = Batas kesalahan (%) Hp = Hasil penunjukkan Hs = Hasil sesungguhnya
3-5 Pemasangan Alat Pembatas dan Pengukur
Jenis/model sambungan APP untuk pelanggan relatif banyak, hal ini disebabkan tingkat keanekaragaman kontrak daya antara PLN dengan pelanggan cukup banyak.
%100)( xHHH
Ss
sp −=
Alat Pembatas dan Pengukur
82
Di tinjau dari besarnya daya maupun tingkat tegangan pada
pelanggan, yaitu pelanggan TT-TM, TM-TM, TM-TR, dan TR-TR baik untuk pasangan luar maupun pasangan dalam. Oleh karenanya disini hanya di tunjukkan beberapa saja dimana sudah dianggap mewakili dari masing-masing jenis tersebut.
Gambar 3-19. Sambungan Listrik 3 Fasa Tarip Ganda Dari Gardu Tiang dengan kabel TR NYFGBY
Alat Pembatas dan Pengukur
85
Gambar 3-22. Sambungan Listrik TM Pengukuran TM Tarif Tunggal Menggunakan peralatan Cubicle dg Kabel TM
Alat Pembatas dan Pengukur
86
Gambar 3-23. Sambungan Listrik TM Pengukuran TM Tarif Ganda Menggunakan peralatan Cubicle dg Kabel TM kVARh
(Sistem 4 kawat)
Alat Pembatas dan Pengukur
88
Gambar 3-25. Sambungan Listrik TM Pengukuran TM Tarif Tunggal Menggunakan Cut Out / Tiang dengan AAAC & KVARH (Sistem 3 kawat)
78 Gambar 4-22. Sambungan Listrik TM Pengukuran TM Tarif Ganda Menggunakan peralatan Cubicle dg Kabel TM
kVARh (Sistem 3 kawat)
Alat Pembatas dan Pengukur
89
Gambar 3-26. Sambungan Listrik TM Pengukuran TR Tarif Tunggal Menggunakan Peralatan Cubicle dengan
Kabel TM & KVARH (Sistem 3 kawat/4 kawat TM)
Alat Pembatas dan Pengukur
90
Gambar 3-27. Lemari APP untuk TM-TR ( 100 A - 500 A) (dengan Tutup Luar)
Alat Pembatas dan Pengukur
91
Gambar 3-28. Lemari APP untuk TM-TR ( 100 A - 500 A) (Tanpa Tutup Luar)
Alat Pembatas dan Pengukur
92
Gambar 3-29. Sambungan Listrik TM Pengukuran TR Tarif Ganda Menggunakan Peralatan Cubicle dengan
Kabel TM & KVARH (Sistem 3 kawat/4 kawat)
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 93
BAB IV JARINGAN DISTRIBUSI TEGANGAN RENDAH
4-1 Tiang Saluran Tegangan Rendah 4-1-1 Jenis Tiang
Pada umumnya tiang listrik yang sekarang digunakan pada SUTR terbuat dari beton bertulang dan tiang besi. Tiang kayu sudah jarang digunakan karena daya tahannya (umumnya) relatif pendek dan memerlukan pemeliharaan khusus. Sedang tiang besi jarang digunakan karena harganya relative mahal dibanding tiang beton, disamping itu juga memerlukan biaya pemeliharaan rutin.
Dilihat dari fungsinya, tiang listrik dibedakan menjadi dua yaitu tiang pemikul dan tiang tarik. Tiang pemikul berfungsi untuk memikul konduktor dan isolator, sedang tiang tarik fungsinya untuk menarik konduktor. Sedang fungsi lainnya disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan posisi sudut tarikan konduktor nya. Bahan baku pembuatan tiang beton untuk tiang tegangan menengah dan tegangan rendah adalah sama, hanya dimensinya yang berbeda. 4-1-2 Menentukan/memilih Panjang Tiang
Gambar 4-1. Konstruksi Tiang Beton
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 94
Tiang beton untuk saluran tegangan menengah dan tegangan rendah dipilih berdasarkan spesifikasi sebagai berikut:
Tabel 4-1. Memilih Panjang Tiang
No. Tegangan Rangkaian Panjang tiang (mtr)
Type(daN)
Span maksimum
1 Menengah Tunggal 11 13
350350
80 120
2 Menengah Ganda 11 13
350350
50 60
3 Rendah Tunggal 99
100200
40 60
10,8 0,25 1,2 TM 9,2 0,25 1,2 TR 1,2 TM 1,2 TR 8,15
6,55
Panjang tiang 13 m 11m
7,5 0,25
7,25
Panjang tiang 9 m
Panel Trafo 4,5 ≈ 5,0
Gambar 4-2. Jarak aman yang diperlukan untuk menentukan panjang tiang
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 95
Pada jaringan tegangan rendah yang menggunakan tiang bersama dengan jaringan tegangan menengah maka jarak gawang (Span) harus di jaga agar tidak lebih dari 60 meter.
Di dalam menentukan panjang tiang beberapa faktor yang harus dipertimbangkan adalah; 1) jarak aman antara saluran tegangan menengah dan tegangan rendah, 2) Posisi trafo tiang, dan 3) tinggi rendahnya trafo dengan penyangga dua tiang. Gambar 4-2 menunjukkan jarak aman yang diperlukan untuk menentukan panjang tiang. Pada gambar tersebut diperlihatkan bahwa panjang tiang minimum untuk tegangan menengah 11 meter (9,2 meter diatas tanah) dan untuk tegangan rendah 9 meter ( 7,5 meter diatas tanah).
4-1-3 Jarak Aman Tiang Tegangan Rendah Dari tabel 5-1 disebutkan bahwa tiang 9 meter type 200 daN dapat
digunakan sampai jarak tiang 60 meter, sedang tiang 9 meter type 100 daN dapat digunakan terbatas sampai jarak tiang 40 meter, bahkan lebih pendek dengan pengurangan beban kawat, karena batas ketahanan momen hampir nol pada pada jarak(span) 40 meter, bila
Tabel 4-2. Batas minimum penggunaan tiang beton Pada jaring SUTR – TIC khusus
Jumlah Jaring SUTR - TIC
Gawang SUTR-TIC (Span) Khusus
50 m Penggunaan Khusus
60 m 75 m
Sirkit Tunggal
3x70+54,6 + 2x16
9/200 9/200 9/200
3x50+54,6 + 2x16 3x35+54,6 + 2x16 3x70+54,6 +1 x16 3x50+54,6 +1 x16 3x35+54,6 +1x16
3 x 70 + 54,6 3 x 50 + 54,6 3 x 35 + 54,6
Sirkit Ganda
3x70+54,6 + 2x16
9/200
9/500
9/500
3x50+54,6 + 2x16 3x35+54,6 + 2x16 3x70+54,6 +1 x16 3x50+54,6 +1 x163x35+54,6 +1x16
9/200
3 x 70 + 54,6 3 x 50 + 54,6 3 x 35 + 54,6
tekanan angin pada konduktor dan tiang mendekati momen ketahanan sebesar 724 kgm. Hal ini dapat di rinci sebagai berikut:
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 96
A: Momen pembengkok oleh tekanan angin pada konduktor = 522 kgm untuk jarak tiang 40 meter.
B: Momen pembengkok oleh tekanan angin pada tiang = 214 kgm
A + B = 736 kgm ÷ 724 kgm. Ini berarti batas momen ketahanan tidak terlampaui untuk penurunan
kawat. Tabel 5-2 menunjukkan batas minimum penggunaan tiang beton pada jaring SUTR –TIC khusus. 4-1-4 Merencanakan dan mempersiapkan mendirikan tiang
Untuk menentukan jumlah (kebutuhan) dan jenis tiang pada suatu lokasi, diperlukan data survai jaringan yang akan dipasang. Dari gambar situasi jaringan dapat ditentukan jenis dan perlengkapan tiang untuk lokasi tersebut, yaitu jumlah tiang TR dan penunjangnya. Tiang beton untuk Tegangan Rendah digunakan ukuran 9 meter, Gambar 4-5 dan gambar berikutnya menunjukkan konstruksi tiang beton dengan perlengkapannya sesuai dengan kebutuhan di lokasi.
Telah diuraikan diatas, jarak antar tiang ditetapkan sebesar 40-60 meter, namun jarak tersebut masih perlu disesuaikan dengan kondisi lokasi (masih bisa digeser). Dari gambar situasi jaringan dapat ditentukan jenis dan perlengkapan yang diperlukan (Material Distribusi Utama) untuk lokasi tersebut, yaitu jumlah tiang beton, konduktor, Kabel tanah dan Udara, serta isolator dan perlengkapannya.
Setelah mengetahui jumlah tiang beton yang diperlukan, selanjut-nya mempersiapkan peralatan minimal yang diperlukan (yang harus disediakan oleh pemborong) untuk pekerjaan mendirikan tiang adalah sebagai berikut:
a. Tool kit lengkap g. Kantong kerja b. Sabuk Pengaman h. Tas kerja c. Derek-tangan i. Topi pengaman d. Besi kaki tiga j. Tampar 16 mm e. Bor tanah k. Linggis dan lain-lain. f. Gerobak (untuk mengangkut tiang) l. Tangga
4-1-5 Mendirikan/menanam Tiang Bagian tiang yang harus ditanam di bawah permukaan tanah adalah
1/6 dari panjang tiang. Jadi kedalaman lubang tergantung panjang/tinggi tiang yang akan dipasang. Pada tanah yang lembek bagian bawah tiang harus di pasang bantalan (beton blok) agar bagian tiang yang tertanam dalam tanah tetap 1/6 panjang tiang. Dari gambar 4-1 tampak bahwa untuk panjang tiang 13 meter bagian yang berada diatas tanah adalah 10,2 meter, untuk panjang tiang 11 meter bagian yang berada diatas tanah adalah 9,2 meter, dan untuk panjang tiang 9 meter bagian yang berada diatas tanah adalah 7,5 meter.
Pekerjaan mendirikan tiang beton diawali dengan menyiapkan gambar rencana penempatan tiang. Dari gambar rencana dapat ditentukan jumlah tiang yang diperlukan dan ditentukan pula letak dimana tiang akan didirikan
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 97
(ditandai dengan patok). Selanjutnya untuk mendiri-kan tiang dapat dilakukan langkah–langah sebagai berikut: 1) Mempersiapkan alat-alat kerja dan perlengkapan yang diperlukan untuk mendirikan tiang tersebut, 2) Mendistribusikan tiang-tiang tersebut ke lokasi dimana letak tiang akan didirikan, 3) Menggali lubang pada setiap tempat yang akan didirikan tiang, 4) Jika galian sudah siap, maka kegiatan mendirikan tiang dapat dilakukan. Mendirikan tiang beton tegangan rendah (9 meter) dapat dilakukan dengan dua cara; pertama secara manual (konvensional), yaitu menggunakan derek-tangan dan dengan menggunakan penyangga (tangga). Cara ini dilaksanakan terutama pada lokasi-lokasi penanaman tiang yang sulit dijangkau dengan mobil derek. Pada tiang tegangan rendah (9 meter) hal ini sangat mungkin terjadi. Mendirikan tiang dengan cara manual dilakukan sebagai berikut: 1) Sebelum tangga untuk penyangga tiang ditinggikan, terlebih dahulu tiang beton diangkat dengan derek-tangan, 2) Mengikatkan rantai derek-tangan pada bagian tengah tiang. Derek-tangan ini digantungkan pada besi kaki tiga yang disiapkan untuk pekerjaan ini. 3) Jika tiang beton sudah mulai dinailkkan, maka diikuti dengan tangga atau penopang yang lain untuk mendorong ke atas. 4) Disamping itu untuk mengendalikan arah tiang beton pada saat diangkat, dipasang tali tampar sebanyak 4(empat) atau 3(tiga) direntangkan ke arah berbeda, diikatkan pada posisi (15-20) % dari ujung atas tiang, untuk mengendalikan arah tiang pada saat diangkat. 5) Selanjutnya tiang ditarik/didorong ke atas sambil dikendalikan dari arah tali tampar tersebut, sampai bagian pangkal tiang mendekati dan masuk
lubang. 6) Untuk tiang beton bertulang sebelum diuruk tanah, perhatikan arah lubang baut untuk penempat an croos arm. 7) Jika arah lubang belum sesuai putarlah tiang dengan mengikatkan tali pada tiang, kemudian tiang diputar sesuai dengan arah lubang tempat baut yang diinginkan. Selanjutnya uruk dengan tanah pada sekitar tiang sampai padat. Untuk tanah yang lembek pada pangkal tiang perlu dipasang pondasi atau diberi bantalan. Kedua, mendirikan tiang dengan alat pengangkat lebih cepat dan praktis, tidak memerlukan
banyak tenaga manusia (lihat Gambar 4-4). Setelah lubang tempat tiang disiapkan, maka tiang cukup diangkat dengan alat pengangkat, dan selanjutnya diperlukan bantuan untuk mengarahkan supaya pangkal tiang
Tiang beton9 meter
Gambar 4-3. Mendirikan tiang cara manual
Besi kaki tiga 3-4”
Tali tampar 16 mm
Tangga
Derek-tangan
Lubang tempat tiang
Ratai di tarik
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 98
tepat berada diatas lubang, kemudian tiang dimasukkan ke dalam lubang. Persyaratan yang lain sehubungan dengan kondisi tanah, sama dengan cara pertama. 4-2 Saluran Tegangan Rendah
Saluran Tegangan Rendah terdiri dari 3(tiga) macam, yaitu Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR), Saluran Kabel Udara Tegangan rendah (SKUTR), dan Saluran Kabel Tanah Tegangan Rendah.
4-2-1 Saluran Udara Tegangan Rendah Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) dengan LVTC (Low
Voltage Twistad Cable), saat ini sudah dikembangkan, hal ini untuk mempertinggi keandalan, faktor keamanan dan lain-lain. Untuk kabel LVTC ini pemasangannya, 1) di bawah SUTM (Underbuilt) dan 2) khusus LVTC (JTR murni). Spesifikasi kabel LVTC seperti tercantum pada tabel 4-3 halaman 99.
- Accesoreis twisted cable terdiri dari : 1. Suspension assembly 2. Large angle assembly 3. Dead end assembly 4. Insulated tap connector berbagai ukuran 5. Insulated Nontension joint 6. Insulated tension joint. 7. Guy set / stay set SUTR Pemakaian guy set pada SUTR digunakan type ringan, pada stay set
SUTR ini tidak mempergunakan guy insulator. Spesifikasi material guy set sesuai dengan gambar standar, sedang
kawat baja galvanisnya sbb. : 1. Ultimate load : 17 kN 2. Penampang : 22 mm2 3. Material : baja
Dalam pemasangan Saluran Udara, konduktor harus ditarik tidak terlalu kencang dan juga tidak boleh terlalu kendor, agar konduktor tidak menderita kerusakan mekanis maupun kelelahan akibat tarikan dan ayunan, dilain pihak dicapai penghematan pemakaian konduktor.
Dalam pemasangan kabel udara setelah tiang berdiri, sambil menggelar kabel dari haspel terlebih dahulu dipasang perlengkapan bantu (klem service), pengikat, pemegang dan sebagainya. Untuk kabel penghantar berisolasi, bagian yang diikat pada pemegang di tiang adalah
Gambar 4-4. Mendirikan Tiang dengan alat pengangkat
Tiang beton
Alat pengangkat
Lubang tempat tiang Tali tampar
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 99
penghantar Nol, baik untuk dua kabel (sistem satu fasa) maupun empat kabel (sistem tiga fasa). Penarikan kabel dimulai dari salah satu tiang ujung, kemudian ditarik dengan alat penegang (hand tracker. Setelah tarikan dianggap cukup kuat, maka pada setiap tiang kabel Nol diikat dengan pemegang yang telah disiapkan.
Sebagaimana diketahui bahwa harga konduktor berkisar 40% dari harga perkilometer jaringan. Batasan-batasannya adalah sebagai berikut:
a) Tarikan AAAC yang diijinkan maksimum 30% dari tegangan putus (Ultimate tensile strength).
b) Tarikan Twisted cable yang diijinkan maksimum 35% dari tegangan putus dari kawat penggantung.
c) Andongan yang terjadi pada SUTR dengan jarak gawang 35-50 meter, tidak boleh lebih dari 1 meter.
Tabel 4-3. Spesifikasi kabel LVTC
Spesifikasi 70 mm2 50 mm2 35 mm2 - Max. Resistivity pada 20O C (mm2/m) 0,0283 0,0283 0,0283 - Minimum tensile strangth (K/mm2) 180 180 180 - Density at 20O C (kg/dm3) 2,7 2,7 2,7 - Koefisien of resistansi exp./ OC 0,004 0,004 0,004 - Cross section (mm2) 70 70 70 - Diameter of bare conductor 10,1 8,4 7 - Tolerance of conductor diameter (%) 5 5 5 - Number of stranded 19 19 19 - Type of insulation XLPE XLPE XLPE - Ketebalan dari isolasi (mm) 18 18 18 - Dia. of cond. over installation (mm) 12,9 - 9,6 - Max. service/s.c. temperature/oC 80/130 80/130 80/130 - Max. arus pada amb. temperatur 205 146 132 - Voltage rating (Volt) 1000/600 1000/600 1000/600 - Berat kg/km 1000 786 550 - DC resistance at 20oC (Ohm/km) 0,443 0,613 0,876
Pada kontruksi jaringan tegangan rendah atau menengah harus
diperhatikan lintasan yang akan dilewati saluran kabel, misalnya pada saat kabel udara melintasi jalan umum, kabel udara yang dipasang di bawah pekerjaan konstruksi, kabel udara melintasi sungai, dan lintasan- lintasan lain yang perlu perhatian sehubungan dengan keamanan kabel dan keselamatan mereka yang berada di sekitar kabel tersebut. Berikut ini adalah beberapa contoh bentuk saluran kabel udara yang melewati lokasi tersebut, dan ukuran-ukuran jarak aman terhadap lingkungan yang tercantum dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakaan tugas pemasangan kabel.
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 100
Gambar 4-5. Kabel udara melintasi jalan umum yang dilalui kendaraan bermotor.
Jarak keamanan H Jalan umum 6 m Penghantar Berisolasi Jalan pribadi 4 m
Wilayah Pribadi 3 m
Gambar 4-6. Kabel udara yang dipasang di sepanjang jalan raya.
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 101
Gambar 4-7. Kabel udara yang dipasang di bawah pekerjaan konstruksi
Gambar 4-8 Dua Kabel
Peralatan proteksi
h > 1 m jika tegangan saluran 2 lebih tinggi dari 130 V dan lebih rendah dari 57 kV h > 2 m jika tegangan saluran 2 lebih tinggi dari 57 kV
Gambar 4-8. Dua Kabel udara (SUTM & SUTR) dipasang pada satu tiang
Saluran 2
Saluran udara kabel twisted TR aluminium
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 104
Gambar 4-12. Kabel udara yang melintasi rel kereta api
Gambar 4-11. Kabel udara melintasi jalur listrik saluran udara
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 105
Gambar 4-13. Kabel udara yang melalui kabel udara telekomunikasi
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 107
Gambar 4-13. Kabel udara yang melalui kabel udara telekomunikasi
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 109
Gambar 4-15. Pemasangan saluran udara di dekat kabel telekomunikasi
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 110
Gambar 4-16. Kabel udara yang melintasi Rel kereta api.
Gambar 4-17. Contoh skema jaringan tegangan rendah
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 111
Gambar 4-18. Pemasangan TC pada jaringan 0o-45o
pada tiang beton bulat (sudut kecil)
No. Kode Jumlah Material 1 2 3 4 5
iss isc ipb ib isp
3 mtr 1 set 1 bh 2 buah2 buah
Stainless Steel Strap Suspension Clamp Pole Bracket Plastic Strap Stopping Buckle
No. Kode Jumlah Material 1 2 3 4 5
iss isc ipb ib isp
3 mtr 2 set 1 bh 2 buah 2 buah
Stainless Steel Strap Strain Clamp Pole Bracket Stopping Buckle Plastic Strap
Gambar 4-19. Pemasangan TC pada jaringan 45o-120o pada tiang beton bulat (sudut besar)
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 112
Keterangan Gambar 4-21: 1. Suspension Clamp Bracket 2. Suspension Clamp 3. Stainless Steel Strip 0,75 Meter
4. Stopping Buckle 5. Plastic Strap 6. Protektip Plastic Strap 0,5 Meter
Gambar 4-21 Konstruksi tiang penyangga(TR1)
Gambar 4-20. Penyambungan TC pada tiang penegang
No. Kode Jumlah Material 1 2 3 4
iss isc ipb ib
3 mtr 2 set 5 bh 2 buah
Stainless Steel Strap Pole Bracket Plastic Strap
Gambar 4-21 sampai dengan Gambar 4-34 , adalah kontruksi tiang penegang saluran udara tegangan rendah (LVTC) sesuai dengan keperluan dimana tiang akan dipasang. Pada masing-masing gambar disertakan daftar perlengkapan/material yang diperlukan sesuai dengan peruntukannya.
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 113
Gambar 4-22 Konstruksi tiang penegang/sudut(TR2)
Keterangan Gambar 4-22: 1. Tension Bracket 2. Strain Clamp 3. Stainless Steel Strip 0,75 Meter 4. Stopping Buckle 5. Plastic Strap 6. Protektip Plastic Strap 0,5 Meter
Gambar 4-23 Konstruksi tiang awal/akhir(TR3)
Gambar 4-24 Konstruksi tiang penyangga silang(TR4)
Keterangan Gambar 4-24: 1. Suspension Clamp Bracket 2. Suspension Clamp 3. Stainless Steel Strip 0,75 Meter 4. Stopping Buckle 5. Plastic Strap 6. Bundled Conductor, Connector 70-25/70-25 7. Protektip Plastic Strap 0,5 Meter
Keterangan Gambar 4-23: 1. Tension Bracket 2. Strain Clamp 3. Stainless Steel Strip 0,75 Meter 4. Stopping Buckle 5. Plastic Strap 6. PVC 2” – 50 Cm 7. Link 8. Dead end tubes 9. Protektip Plastic Strap 0,5 Meter
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 114
Gambar 4-26 Konstruksi tiang penyangga & sudut silang (TR4B)
Keterangan Gambar 4-26: 1. Tension Bracket 2. Strain Clamp 3. Stainless Steel Strip 0,75 Meter 4. Plastic Strap 5. Stopping Buckle 6. Bundled Conductor, Connector 70-25/70-25 7. Protektip Plastic Strap 0,5 Meter
Kode pada Gambar Distribusi
Gambar 4-27. Konstruksi tiang penegang (TR5)
Keterangan Gambar 4-27: 1. Tension Bracket 2. Strain Clamp 3. Stainless Steel Strip 0,75 Meter 4. Stopping Buckle 5. Plastic Strap 6. Protektip Plastic Strap 0,50 Meter
Kode pada Gambar Distribusi
Keterangan Gambar 4-25: 1. Tension Bracket 2. Strain Clamp 3. Stainless Steel Strip 0,75 Meter 4. Plastic Strap 5. Stopping Buckle 6. Bundled Conductor, Connector 70-25/70-25 7. Suspension Clamp Bracket 8. Suspension Clamp 9. Protektip Plastic Strap 0,5 Meter
Kode pada Gambar Distribusi Gambar 4-25 Konstruksi tiang
penyangga & sudut silang (TR4A)
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 115
Gambar 4-28. Konstruksi tiang penegang dengan hantaran beda penampang (TR5A)
Keterangan Gambar 4-29: 1. Suspension Clamp Bracket 2. Suspension Clamp 3. Tension Bracket 4. Strain Clamp 5. Stainless Steel Strip 0,75 Meter 6. Stopping Buckle 7. Plastic Strap 8. Bundled Conductor, Connector 70-25/70-25 9. Protektip Plastic Strap 0,5 Meter
Kode pada Gambar Distribusi Gambar 4-29. Konstruksi tiang percabangan (TR6)
Keterangan Gambar 4-28: 1. Tension Bracket 2. Strain Clamp 3. Stainless Steel Strip 0,75 Meter 4. Stopping Buckle 5. Plastic Strap 6. Bundled Conductor, Connector 70-25/70-25 7. Protektip Plastic Strap 0,50 Meter
Kode pada Gambar Distribusi
Kode pada Gambar Distribusi
Keterangan Gambar 4-30: 1. Tension Bracket 2. Strain Clamp 3. Stainless Steel Strip 0,75 Meter 4. Plastic Strap 5. Stopping Buckle 6. Bundled Conductor, Connector 70-25/70-25
Gambar 4-30. Konstruksi tiang percabangan (TR6A)
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 116
Keterangan Gambar 4-31: 1. Tension Bracket 2. Strain Clamp 3. Stainless Steel Strip 0,75 Meter 4. Stopping Buckle 5. Plastic Strap 6. Line tap Connector 70-25/70-25
Kode pada Gambar Distribusi
Gambar 4-31 Konstruksi Penyambungan konduktor TC
dan AAAC (TR7)
Keterangan Gambar 4-32: 1. Guy Wire Band + Bolt & Nut M16 x 50 2. Turn Buckle 3. Preformet Grip 22/35/55/70 Sqmm 4. Guy Insulator 5. Galv. Steel Stranded Wire 22/35/55/70 6. Wire Clip 7. Pipa pelindung ¾” – 2mtr 8. Guy Rod 2,5 Mtr 9. Guy Rod 1,8 Mtr
10. U Bolt & Nut M 16 11. Anchor Block 500 x 500 mm 12. Expanding Anchor 13. Span Schroef 5/8”
Gambar 4-32 Konstruksi Guy Wire (GW)
Type Tiang
Galv. Steel Stranded Wire (X)
11 Mtr 13 Mtr 9 Mtr 11 Mtr 7 Mtr 9 Mtr
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 117
No.Type Tiang Satuan dalam meter
Utama Strut Pole A B C D E
1 11 11 8,4 10 5,42 1,83 1 2 11 9 7,7 8,4 3,3 1,83 0,63 9 9 6,75 8 4,2 1,5 1 4 7 7 5,3 6,5 3,7 1,16 0,5
TIANG UTAMA
HANTARAN AAAC 3X(SQM)35 70 150 240
11-350 9-200 9-200 9-200 11.20011-200 9-200 9-200 11.200 9-200 7-100 9-100
No. Nama Material 1. Strut Arm Band + Bolt & Nut M 16x50 2. Strut Arm 3. Pipa Galvaniz φ 2” – 1,5 Mtr 4. Single GW Band + Bolt & Nut M 16x75 5. Bolt & Nut M 16 x 75
Keterangan: Type tiang Galv. Steel Stranded Wire (X) TM-9 Mtr 30 Mtr TR-9/7 Mtr 28 Mtr
No. 11 Dipasang sebagai pengganti No. 8, 9, 10, 13
Keterangan Gambar 4-18: 1. Guy Wire Band + Bolt & Nut M16 x 50 2. Turn Buckle 3. Preformet Grip 22/35/55/70 Sqmm 4. Guy Insulator 5. Galv. Steel Stranded Wire 22/35/55/70 6. Wire Clip 7. Pipa pelindung ¾” – 2mtr 8. Guy Rod 2,5 Mtr 9. U Bolt & Nut M 16
10. Anchor Block 500 x 500 mm 11. Expanding Anchor 12. Span Schroef 5/8” 13. Guy Rod 1,8 Mtr
Gambar 4-34 Konstruksi Horizontal Guy Wire (GW)
Gambar 4-33 Konstruksi Strut Pole
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 118
4-2-2 Memasang Saluran Kabel Udara Tegangan Rendah 4-2-2-1 Persiapan Pelaksanaan Penggelaran Kabel Tanah
1). Persiapan gambar rencana pelaksanaan pada peta 1 : 5000 atau 1: 200 2). Survai dalam pembersihan jalur kabel. 3). Penggalian titik kontrol jalur kabel pada tiap 50 meter (injeksi test galian) untuk meneliti kemungkin- an adanya utilitas lain. 4). Check dokumentasi asbuilt drawing utilitas- utilitas lain. 5). Persiapan material penunjang (Pasir urug, Batu patok/tanda, Batu peringatan, Pipa beton/ PVC/sejenis). 6). Pekerjaan pendahuluan telah dilaksanakan Lintasan/Crossing-Boring,
Jembatan kabel, Pembersihan rencana jalur kabel, Rambu-rambu K3, Alat-alat kerja (rol kabel, dan lain-lain).
7). Pelaksanaan penggelaran/penarikan kabel dengan 1 supervisor, 1 mandor, 1 kuli tiap 5 meter.
8). Berikut ini adalah gambar-gambar alat angkut untuk menunjang pemasangan kabel tanah.
Gambar 4-36 Kendaraan pengangkut kabel dan haspel (gulungan kabel)
Gambar 4-35 Alat pelindung dari seng
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 119
4-2-2-2 Perkakas kerja dan penggunaannya. 1) Pemakaian perkakas kerja dengan tepat. Apabila kita dapat menggunakan perkakas kerja dengan tepat, maka
di dalam melaksanakan pekerjaan tersebut akan memperoleh manfaat sebagai berikut; 1) Efisiensi kerja meningkat, 2) Jumlah pemakaian/pengerahan tenaga kerja yang berkurang, 3) waktu pelaksanaan menjadi lebih pendek / pekerjaan cepat terselesaikan, 4) Kualitas pekerjaan lebih baik, 5) Pembiayaan menurun, 6) Menaikkan daya saing.
2) Efisiensi akibat penggunaan perkakas sederhana. Perlu diketahui bahwa untuk melaksanakan pekerjaan besar dengan
hanya memakai alat yang sederhana sudah tak efisien lagi. Contoh: a) Untuk melaksanakan koneksi kabel pada suatu gardu kontrol dimana jumlah kabel mencapai ratusan jalur, maka pengupasan kabel dengan pisau akan memerlukan waktu sangat lama, karena itu harus memakai tang pengupas kabel. b) Untuk pemasangan label yang tertanam di dalam rumah dengan volume pekerjaan yang sangat besar, maka penggalian saluran kabel dengan memakai alat konvensional seperti cangkul, sekop atau linggis saja, hasilnya sangat tidak efisien. Untuk menanggulangi hal ini maka penggalian harus memakai alat pengeruk yang berkapasitas besar (misalnya menggunakan Back Hoe). c) Pemasangan transformator tenaga dengan daya puluhan Mega Watt membutuhkan bantuan mobil derek dan mobil trailer dengan daya angkat puluhan ton.
Perlu diketahui bahwa dalam melaksanakan proyek/pekerjaan di Indonesia, banyak alat kerja yang cepat rusak, hal ini disebabkan karena pemakai, kurang tahu cara pemakaian atau pemakainya yang serampangan, serta tata cara pemeliharaan yang kurang diperhatikan. Contoh: a) Membuat lubang besar pada plat besi dengan memakai bor listrik dengan mata bor yang kecil dengan menggoyang-goyangkan mata bornya, hal ini akan merusak mesin bor listrik tersebut. B) Mengukur arus besar suatu beban listrik dengan memakai Ampere Meter yang mempunyai kapasitas arus kecil akan merusak alat ini.
3) Kemampuan menggunakan perkakas kerja. Mengingat harga peralatan relatif mahal, bahkan kadang-kadang
harus dipesan dari luar negeri dan memerlukan waktu yang cukup lama, apabila alat mengalami kerusakan dan tidak bisa dipakai, akan mengganggu jalannya pekerjaan. Oleh karenanya kemampuan orang yang menggunakan alat tersebut harus memadai benar-benar terlatih.
Untuk pemakaian alat kerja khusus, dimana diperlukan ketelitian dan rumit, misal : mencari lokasi gangguan kabel tanah dengan
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 120
menggunakan Jembatan Wheatstone, maka calon pemakai harus dilatih terlebih dahulu mengenai cara pemakaian alat tersebut.
Hal penting yang harus diperhatikan, alat kerja di lapangan harus dikelola dengan baik, terutama pada proyek-proyek besar, dimana alat kerja harus dikelola oleh pengelola material (Material Controller) dan pengatur alat kerja (Tool Kipp) mulai dari pemesanan, penerimaan barang, pemakaian keluar masuk gudang dan pemeliharaan alat kerja tersebut.
Untuk menanggulangi hal tersebut diatas, tenaga kerja bidang teknik listrik harus mampu memakai alat dengan baik, demikian juga dalam memeliharanya.
4) Pengelompokan dan penggunaan perkakas kerja. Perkakas kerja dapat dikelompokkan menjadi 4(empat), yaitu
Perkakas, Alat Ukur dan Tes, Alat Pengaman, dan Alat Bantu.
Untuk mempermudah pengelompokan/pemilahan alat kerja suatu proyek, berikut ini diberikan nama dan gambar peralatan untuk berbagai pekerjaan. Suatu proyek besar memerlukan alat kerja khusus yang tidak terdapat di lokasi. Oleh karena itu pengadaan alat tersebut harus dijadwalkan dengan tepat waktu.
Tekniksi listrik yang memasang instalasi listrik dalam bangunan, dituntut keterampilan dalam berbagai bidang pekerjaan di bangunan tersebut. Hal ini meliputi teknik menandai, memotong, memahat dan menggergaji.
5) Berikut ini adalah gambar-gambar alat perkakas yang harus disiapkan oleh pelaksana sebelum melaksanakan pekerjaan penanaman kabel tanah. Alat kerja yang tercantum disini cukup lengkap, tetapi untuk pemakaian di proyek disesuaikan dengan kebutuhan.
Gambar 4-38 Kotak Perkakas (Tool box)
Gambar 4-37Kantung Perkakas Tukang Listrik
(Electrician tool pouche)
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 121
Gambar 4-39 Belincong (Pick)
Gambar 4-43 Bor Tangan (Hand drill)
Gambar 4-40 Bor Listrik (Electric drill)
Gambar 4-42Bor Nagel
(Auger (Ginlet)
Gambar 4-41 Cangkul (Shovel)
Gambar 4-45Gergaji kayu
Gambar 4-44Gergaji kayu (stang)
Gambar 4-46 Kakatua
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 122
Gambar 4-49 Kikir (File) Gambar 4-48 Kunci Inggris
( Adjustable Wrech)
Gambar 4-50 Kunci Pas (Spanner)
Gambar 4-51 Kunci Ring (Offset Wrech)
Gambar 4-47 Linggis (Digging Bar)
Gambar 4-53 Obeng (Screw Driver)
Gambar 4-52 Pahat Beton
(Concrete Chisel)
Gambar 4-54Pahat Kayu
(Wood Chisel) Gambar 4-55 Palu (Hammer)
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 123
Gambar 4-56 Penjepit Sepatu Kabel Hidrolik
(Hydraulic Crimping Tool) Gambar 4-57
Alat Pembengkok Pipa (Pipe Bender)
Gambar 4-59 Pisau Kupas Kabel (Line’s men knive)
Gambar 4-58Sendok Aduk (Trowel)
Gambar 4-60Skop ( Spade )
Gambar 4-61 Tang Kombinasi
(Master Plier)
Gambar 4-62Tang Lancip
(Radio long Nose Plier)
Gambar 4-63 Tang Pengupas Kabel
(Wire Striper)
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 124
6) Berikut ini adalah gambar-gambar alat ukur dan tes pemasangan instalasi listrik. Alat ukur yang tercantum disini cukup lengkap, tetapi untuk pemakaian di proyek disesuaikan dengan kebutuhan.
Gambar 4-64 Tang Potong
(Diagonal cutting plier) Gambar 4-65
Tirpit (Penarik kabel)
Gambar 4-66Ampere Meter
Gambar 4-67 Kwh Meter
Gambar 4-68Lux Meter
(Illumino Meter) Gambar 4-69
Megger (Insulation Tester)
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 125
Gambar 4-70Meteran Kayu/lipat
(Folding wood measurer)
Gambar 4-71 Meteran Pendek (Convec Rule)
Gambar 4-72Multimeter
(Multy meter)
Gambar 4-75Water Pas
(Level)
Gambar 4-74Tespen
(Electric tester)
Gambar 4-73 Termometer
(Thermometer)
Gambar 4-76 Volt meter
(Volt meter)
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 126
7) Berikut ini adalah gambar alat-alat kerja untuk pemasangan instalasi listrik. Ukur dan tes pemasangan instalasi listrik.
Gambar 4-77Kacamata Pengaman
(Safety goole)
Gambar -78 Pelindung Kedengaran
(Hearing protector)
Gambar 4-79Pelindung Pernafasan (Dust/Mist Protector)
Gambar 4-81Sabuk Pengaman (Safety Belt)
Gambar 4-80 Topi Pengaman
(Safety Helmet/Cap)
Gambar 4-82Sarung Tangan 20 kV
(20 kV Glove)
Gambar 4-83 Sepatu Pengaman
(Safety Shoe)
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 127
8) Berikut ini adalah gambar alat-alat bantu pemasangan instalasi listrik.
Gambar 4-85 Catok (Vise)
Gambar 4-87 Disel Genset (Diesel Generator)
Gambar 4-86Dongkrak Haspel Kabel
(Cable Drum Jack)
Gambar 4-84Bor Listrik Duduk
(Bend Electric Drill)
Gambar 4-88 Gerinda Potong Cepat (High Speed Cutter )
Gambar 4-89 Mesin Penarik Kabel (Winche)
Gambar 4-90Molen Beton (Concrete Mixer)
Gambar 4-91Pembengkok Pipa Hidrolis
(Hydraulic Pipe Bender)
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 128
4-3 Memasang Instalasi Pembumian 4-3-1 Definisi-Definisi Sistem Pembumian
Sesuai dengan PUIL 2000 (Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000) terdapat beberapa definisi yang perlu diperhatikan, yaitu :
- Bumi (Earth) adalah massa konduktif bumi yang potensial listriknya di setiap titik manapun menurut konvensi, sama dengan nol.
- Elektrode Bumi (Earth Electrode) adalah bagian konduktif atau kelompok bagian konduktif yang membuat kontak langsung dan memberikan hubungan listrik dengan bumi.
- Gangguan Bumi (Earth Fault) merupakan : 1). Kegagalan isolasi antara penghantar dan bumi atau kerangka.
Gambar 4-92Pemegang Kabel
(Cable Grip)
Gambar 4-93 Pompa Air (Water Pump)
Gambar 4-94Rol Kabel (Cable Roller)
Gambar 4-95 Tangga Geser
(Extension Ladder) Gambar 4-96Treller Haspel Kabel (Cable Drum Trailler)
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 129
Gangguan yang disebabkan oleh penghantar yang terhubung ke bumi atau karena resistansi isolasi ke bumi menjadi lebih kecil dari pada nilai tertentu.
- Isolasi (Insulation) adalah : 1). (Sebagai bahan) merupakan segala jenis bahan yang dipakai
untuk menyekat sesuatu. 2). (Pada kabel) merupakan bahan yang dipakai untuk menyekat
penghantar dari penghantar lain dan dari selubungnya, jika ada, - Elektrode Batang adalah elektrode dari pipa logam, baja profil atau
batang logam lainnya yang dipancangkan ke bumi. - Pembumian (Earthing) adalah penghubung suatu titik sirkit listrik atau
suatu penghantar yang bukan bagian dari sirkit listrik dengan bumi menurut cara tertentu.
- Penghantar pembumian (Earthing Conductor) adalah : 1). Penghantar berimpedasi rendah yang dihubungkan ke bumi. 2). Penghantar proteksi yang menghubungkan terminal pembumian
utama atau batang ke elektrode bumi. - Rel pembumian adalah batang penghantar tempat menghubungkan
beberapa penghantar pembumian.
4-3-2 Jenis Tanah Jenis tanah menurut PUIL 2000 dibagai atas : 1). Tanah rawa, 2). Tanah liat dan tanah ladang, 3). Pasir basah, 4). Krikil basah, 5). Pasir dan kerikil kering, 6). Tanah berbatu.
4-3-3 Tahanan Jenis Tanah Masing-masing jenis tanah mempunyai nilai tahanan jenis tanah yang berbeda-beda dan bergantung dari jenis tanahnya, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini, merupakan nilai tipikal.
Tabel 4-4. Tahanan Jenis Tanah 1 2 3 4 5 6 7
Jenis tanah
Tanah rawa
Tanah liat danTanah ladang
Pasir basah
Kerikilbasah
Pasir dan Kerikil kering
Tanah berbatu
Resistansi jenis
(Ω – m) 30 100 200 500 1000 3000
4-3-4 Tahanan pembumian Tahanan pembumian dari elektrode bumi, tergantung pada jenis tanah dan keadaan tanah serta ukuran dan susunan elektrode.
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 130
Dari Tabel Tahanan Pembumian pada tahanan jenis (rho – 1) = 100 ohm-meter dibawah ini, menunjukkan nilai rata-rata tahanan elektrode bumi, untuk panjang tertentu.
Tabel 4-5. Nilai rata-rata Tahanan Elektrode Bumi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jenis elektrode
Pita atau penghantar pilin Batang atau pipa
Pelat vertikal dengan sisi atas ± 1 m
dibawah Permukaan tanah
10 25 50 100 1 2 3 5 0,5 x 1 1 x 1 Resistans pembumian (Ω)
20 10 5 3 70 40 30 20 35 25
Untuk tahanan jenis pembumian yang lain (rho), maka besar tahanan
pembumiannya merupakan perkalian nilai dalam tabel dengan : Rho / rho – 1 atau Rho / 100
4-3-5 Perencanaan pemasangan peralatan 4-3-5-1 Tujuan Pembumian Peralatan
Pembumian peralatan adalah pembumian bagian dari peralatan yang pada kerja normal, tidak dilalui arus. Tujuan pembumian peralatan adalah :
a). Untuk membatasi tegangan antara bagian-bagian peralatan yang tidak dilalui arus dan antara bagian-bagian ini dengan bumi sampai pada suatu harga yang aman (tidak membahayakan) untuk semua kondisi operasi normal.
b). Untuk memperoleh impedansi yang kecil/rendah dari jalan balik arus hubung singkat ke tanah.
Kecelakaan pada personil, timbul pada saat hubung singkat ke tanah terjadi. Jadi bila arus hubung singkat ke tanah itu dipaksanakan mengalir melalui impedansi tanah yang tinggi, akan menimbulkan perbedaan potensial yang besar dan berbahaya. Juga impedansi yang besar pada sambungan-sambungan pada rangkaian pembumian dapat menimbulkan busur listrik dan pemanasan yang besarnya cukup menyalakan material yang mudah terbakar.
4-3-5-2 Pemasangan dan Susunan Elektrode Bumi Untuk memilih macam elektrode bumi yang akan dipakai, harus
diperhatikan terlebih dahulu kondisi setempat, sifat tanah dan tahanan pembumian yang diijinkan. Permukaan elektrode bumi harus berhubungan baik dengan tanah sekitarnya. Batu dan kerikil yang langsung mengenai elektrode bumi, akan memperbesar tahanan pembumian. Elektrode batang, dimasukkan tegak lurus ke dalam tanah
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 131
dan panjang disesuaikan dengan tahanan pembumian yang diperlukan. Tahanan pembumian sebagian besar tergantung pada panjangnya dan sedikit bergantung pada ukuran penampangnya. Jika beberapa elektrode diperlukan untuk memperoleh tahanan pembumian yang rendah, maka jarak antara elektrode tersebut minimum harus dua kali panjangnya. Jika elektrode tersebut tidak bekerja efektif pada seluruh panjangnya, maka jarak minimum antara elektrode, harus dua kali panjang efektifnya. Penghantar bumi harus dipasang sambungan yang dapat dilepas untuk keperluan pengujian tahanan pembumian, pada tempat yang mudah dicapai dan sedapat mungkin memanfaatkan sambungan yang karena susunan instalasinya memang harus ada. Sambungan penghantar bumi elektrode bumi, harus kuat secara mekanis dan menjamin hubungan listrik dengan baik, misalnya dengan menggunakan las, klem atau baut kunci yang tidak mudah lepas. Klem pada elektrode pipa, harus menggunakan baut dengan diameter minimal 10 mm.
4-3-5-3 Alat Ukur dan Pemeliharaan Tahanan Pembumian a) Alat Ukur Tahanan Pembumian
Untuk mengukur nilai tahanan pembumian dengan cara : 1). Memakai model empat terminal (Motode Wenner) dengan
generator putar tangan (DC).
Gambar 4-97. Alat Ukur Model Wenner
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 132
2). Pengukuran tahanan pembumian dengan menyambungkan terminal C1 ke E yang akan diukur, terminal P2 ke P dan terminal C2 ke R. Jarak E – P – R di buat berjarak sama pada satu garis lurus. Meter akan memberikan pembacaan langsung dalam tahanan dan tahanan pembumian dihitung dengan rumus :
ρ (Rho) = 2 . ∏ . a . R (ohm-m) dimana : ρ (Rho) = resistivitas tanah (ohm-m) a = jarak antara electrode (meter) R = tahanan (ohm) ∏ (Phi ) = 3,14
3). Memakai Earth Tester (analog) berdasarkan harga potensial.
E (elektrode tanah) yang akan diukur dan elektrode bantu P serta elektrode bantu R diletakkan pada satu garis lurus dengan elektrode E. Volt meter akan menunjuk pada potensial E – P. Menurut hukum Ohm, beda potensial akan berbanding langsung dengan tahanan pembumian. Terlihat bahwa tahanan membesar dengan kedudukan P semakin jauh dari E, dan kenaikan tersebut dengan cepat berkurang dan bahkan pada jarak tertentu dari E, kenaikan dapat diabaikan karena sangat kecil.
Persyaratan yang harus diperhatikan adalah : a). Elektrode R harus cukup jauh dari elektrode E, sehingga daerah
tahanan tidak saling menutup (over lap). b). Elektrode P harus ditempatkan di luar dua daerah tahanan, dalam
hal ini ditempatkan pada daerah datar dari kurva. c). Elektrode P harus terletak diantara elektrode-elektrode R dan E,
pada garis penghubungnya.
Gambar 4-98. Mengukur Tahanan Tanah dengan Earth Tester Analog
Sumber Tegangan
AC
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 133
Gambar 4-99. Pengukuran dengan Earth Resistance Tester dan Persyaratan pengukuran tahanan tanah
Gambar 4-100. Pengukuran dengan Tang Ground Tester Digital
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 134
Gambar 4-101. Pemasangan Multyple Grounding
Gambar 4-102. Penempatan Elektrode Pengukuran
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 135
4-3-5-4 Pemeliharaan Tahanan Pembumian Pemeliharaan pembumian (pentanahan) dilaksanakan minimal sekali
dalam setahun diadakan pengukuran nilai pembumian pada musim kemarau. Diambilnya pengukuran pada musim kemarau, karena pada kondisi tersebut nilai tahanan pembumian akan menunjukkan nilai sebenarnya. Jika nilai tahanan pembumian, pada pengukuran di musim kemarau sudah kecil, maka dimusim penghujan akan semakin kecil.
Untuk mengetahui nilai tahanan total pembumian, dipakai rumus :
1/Rp = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + ........................... + 1/Rn (Ohm)
PT. PLN (PERSERO) SOP
MEMELIHARA INSTALASIGARDU TIANG
Kode Unit : DIS.HAR.024(2).A
Halaman 1/5
PETUGAS :
1. Pengawas 1 orang 2. Pelaksana 3 orang
WAKTU PELAKSANAAN : 2 JAM
KOORDINASI :
1. Koordinator Perencanaan Pemeliharaan 2. Koordinator Operasi 3. Koordinator Pemeliharaan 4. Koordinator Perbekalan 5. Asman Distribusi 6. Pelanggan
PERALATAN KERJA :
1. Toolkit Set. 2. Tang Press. 3. Kain Lap, Kuas. 4. Alat Gounding. 5. Fuse Puller
PERALATAN UKUR : 1. Tang Ampere Meter. 2. Volt Ampere Meter. 3. Megger. 4. Earth Tester. 5. Fase Sequance Detector/Drivel.
PERALATAN K-3 :
1. Helm Pengaman. 2. Sepatu Karet. 3. Sarung Tangan Kulit. 4. Pakaian Kerja. 5. P-3 K
MATERIAL/ALAT BANTU :
1. NT/NH Fuse sesuai ukuran 2. Fuse Holder 3. Vaselin/Grease 4. Sepatu Kabel 5. Cat Pilok Warna : Merah, Kuning, Biru, dan Hitam
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 136
PROSEDUR KERJA :
1. Pelaksanaan pemeliharaan atas dasar PK dari atasan yang berwenang. 2. Lakukan pemeriksaan ke lokasi, untuk dasar persiapan pekerjaan. 3. Siapkan alat kerja, alat K-3 dan material kerja yang diperlukan. 4. Konfirmasikan tanggal dan jam pemadaman. 5. Laksanakan pekerjaan sesuai dengan jadual yang sudah disepakati. 6. Selesai melaksanakan pekerjaan, segera menormalkan tegangan. 7. Buat laporan tertulis kepada atasan yang menugsakan.
LANGKAH KERJA :
1. Petugas pelaksana menerima PK dari Asman Distribusi untuk melakukan pemeliharaan Instalasi Gardu Tiang.
2. Menyiapkan Alat Kerja, Alat Ukur, Alat K-3, Material Kerja dan Alat Bantu sesuai dengan kebutuhan.
3. Setelah Petugas sampai di lokasi, gunakan Alat K-3 dan selanjutnya lapor ke Posko petugas akan melakukan pemeliharaan.
4. Melakukan pengukuran arus beban, tegangan fasa dengan fasa dan tegangan fasa dengan nol di Rel dan mencatat dalam formulir BA.
5. Melepas beban jurusan, Fuse Utama, Saklar Utama dan CO sesuai prosedur K-3.
6. Grounding semua kabel jurusan dengan menggunakan Grounding Cable TR.
7. Memeriksa dan menyesuaikan fuse link dengan trafo terpasang dan berikan Vaselin pada kontak dekselnya.
8. Melepas terminasi kabel grounding titik netral pada bushing sekunder transformator, mengukur dan mencatat nilai tahanan isolasi trafo (Primer terhadap Body, Sekunder terhadap Body, Primer terhadap Sekunder) dalam formulir berita acara (BA).
9. Memasang kembali terminasi kabel grounding titik netral pada bushing sekunder transformator dan memeriksa kekencangan mur/baut pada Bushing transformator, bila ada sepatu kabel yang rusak diperbaiki atau diganti baru.
10. Membersihkan Rel, dudukan Fuse Holder, Pisau Saklar Utama (Main Switch), Sepatu Kabel dari kotoran/korosi. Dan bersihkan ruangan dalam Panel Hubung Bagi.
11. Mengukur dan mencatat nilai tahanan isolasi antar Rel, Rel terhadap Body dan Tahanan Pentanahan dalam formulir Berita Acara (BA).
12. Memeriksa kekencangan mur/baut pada Saklar Utama, Sepatu Kabel, Rel, Fuse Holder, Kondisi Isolator Binnen dan Sistim Pembumian.
13. Bila ada komponen PHB-TR yang rusak maka diperbaiki atau diganti baru.
14. Memberi Vaselin pada Pisau Saklar Utama dan Terminal Fuse Holder. 15. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan secara visual, dan
mengamankan seluruh Peralatan Kerja. 16. Melepaskan Grounding Kabel pada seluruh kabel jurusan. 17. Melaporkan pada Posko bahwa pekerjaan pemeliharaan telah selesai,
meminta ijin memasukkan CO sesuai prosedur K-3. 18. Mengukur besar tegangan fasa-fasa, tegangan fasa-nol di Rel dan
putaran fasa sesuai prosedur K-3. 19. Melakukan dan menyesuaikan rating fuse utama dan fuse jurusan.
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 137
20. Masukkan Saklar Utama, Fuse Utama dan Fuse jurusan secara bertahap sesuai prosedur K-3.
21. Melakukan pengukuran beban dan mencatat dalam formulir BA. 22. Menutup dan mengunci pintu PHB-TR. 23. Melepaskan Alat K-3 yang sudah tidak dipergunakan lagi,
membersihkan dan menyimpan kembali pada tempat yang sudah disediakan.
24. Melapor ke Posko, bahwa pekerjaan memelihara instalasi Gardu Tiang telah selesai dan Petugas akan meninggalkan lokasi pekerjaan.
25. Membuat Laporan Berita Acara pelaksanaan pekerjaan. 26. Melaporkan penyelesaian pekerjaan dan penyerahan Formulir BA
kepada Asman Distribusi.
PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI ............
SOP MEMELIHARA INSTALASI
GARDU TIANG
Kode Unit : DIS.HAR.024(2).A
Halaman 1/5
1. DATA LOKASI GARDU TRAFO 1.1. Nomor Gardu : .............................................................. 1.2. Lokasi : .............................................................. 1.3. Daya Trafo
Terpasang : .................................. kVA
1.4. Jumlah Jurusan : .................................. Jurusan 1.5. Konstruksi Gardu : Satu Tiang/Dua Tiang/Gardu Bangunan
Gambar 4-103. Diagram Satu Garis PHB-TR
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 138
2. URAIAN PEKERJAAN :
2.1. Pengukuran Tegangan dan Arus
No Uraian Tegangan ( Volt) R - N S - N T - N R - T S - T 1 Sebelum Har 2 Sesudah Har 2.2. Pengukuran Arus Beban Sebelum Pemeliharaan No. Beban Arus ( Ampere ) R S T N 1 Total 2 Jurusan A 3 Jurusan B 4 Jurusan C 5 Jurusan D 2.3. Pengukuran Arus Beban Sesudah Pemeliharaan No. Beban Arus ( Ampere ) R S T N 1 Total 2 Jurusan A 3 Jurusan B 4 Jurusan C 5 Jurusan D
PT. PLN ( PERSERO ) DISTRIBUSI ......
SOP MEMELIHARA
INSTALASI GARDU TIANG
Kode Unit : DIS.HAR.024(2).A
Halaman 1/5
2.4. Pemeriksaan dan Penyesuaian Fuse Link 1. Nilai Fuse Link
Terpasang/Sebelum Perbaikan
: ......... Ampere
2. Nilai Fuse Link
Sesudah Perbaikan
: ......... Ampere
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 139
2.5.
Pengukuran Tahanan Isolasi Trafo
NO URAIAN Hasil Pengukuran CATATAN R S T 1 Primer 2 Sekunder 3 Primer - Sekunder 2.6. Pengukuran Tahanan Pembumian 1. Nilai Tahanan
Pembumian Sebelum Perbaikan
: ............. Ohm
2. Nilai Tahanan Pembumian Sesudah Perbaikan
: ............. Ohm
3. Nilai Tahanan Setelah Penambahan/Metode Lainnya
: ............. Ohm
2.7. Pemeriksaan Urutan Fasa 1. Sebelum Pemeliharaan : Sesuai / Tidak Sesuai 2, Sesudah Pemeliharaan : Sesuai / Tidak Sesuai
Surabaya,.......................... Manager UPJ/UJ .............. PETUGAS,
( .........................................) ( .......................................)
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 140
PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI .........
SOP MEMELIHARA
INSTALASI GARDU TIANG
Kode Unit : DIS.HAR.024(2).A
Halaman 1/5
PETUGAS :
1. Pengawas 1 orang 2. Pelaksana 2 orang
KOORDINASI :
1. Koordinator Perencanaan Pemeliharaan 2. Koordinator Pemeliharaan JTR 3. Koordinator Perbekalan 4. Asman Pemeliharaan 5. Pelanggan
PERALATAN KERJA : 1. Toolkit Set. 2. Tang Press. 3. Palu 3 Kg. 4. Cangkul, Tali. 5. Gergaji Besi 6. Pengencang Stainless Steel
PERALATAN UKUR : 1. Earth Tester
PERALATAN K-3 :
1. Helm Pengaman. 2. Sepatu Karet. 3. Sarung Tangan Kulit. 4. Pakaian Kerja. 5. Sabuk Pengamana 6. P-3 K
MATERIAL/ALAT BANTU :
1. Ground Rod 2. BC 50 mm2 3. Klem Pentanahan 4. Pipa Galvanis 5. Stainless Steel Strap dan Stopping Buckles 6. CCO (Connector Al/Cu)
PROSEDUR KERJA :
1. Pelaksanaan pemeliharaan atas dasar PK dari atasan yang berwenang.
2. Lakukan pemeriksaan ke lokasi, untuk dasar persiapan pekerjaan. 3. Siapkan alat kerja, alat K-3 dan material kerja yang diperlukan. 4. Konfirmasikan tanggal dan jam pelaksanaan pemeliharaan. 5. Laksanakan pekerjaan sesuai dengan jadual yang sudah disepakati. 6. Selesai melaksanakan pekerjaan, segera melaporkan kepada Posko. 7. Buat laporan tertulis kepada atasan yang menugsakan.
LANGKAH KERJA :
1. Petugas pelaksana menerima PK dari Asman Distribusi untuk melakukan pemeliharaan Sistim Pembumian (arde) Jaringan Tegangan Rendah.
2. Siapkan Alat Kerja, Alat Ukur, Alat K-3, Material Kerja dan Alat Bantu sesuai dengan kebutuhan.
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 141
3. Setelah Petugas sampai di lokasi, gunakan Alat K-3 pasang rambu peringatan untuk publik dan selanjutnya lapor ke Posko bahwa petugas akan melakukan pemeliharaan sistim pembumian (arde) JTR.
4. Periksa sambungan-sambungan dan kawat arde sistim pentanahan secara visual.
5. Apabila terdapat kelainan misalnya putus atau hilang maka gantilah dengan penghantar yang baru dengan cara menghubungkan kawat arde dengan netral JTR sementara ujung yang lain biarkan tidak terhubung dengan Ground Rod.
6. Lakukan pengukuran Tahanan Pentanahan/Ground Rod sesuai dengan instruction manual dan catat nilai tahanannya di Formulir BA.
7. Bila hasil pengukuran nilai tahanan > 5 Ohm lakukan dengan menambah atau memperdalam Ground Rod. Atau dengan metode lain.
8. Lakukan pengukuran ulang dan catat nilai tahanan pentanahan di formulir Berita Acara (BA).
9. Lakukan penyembungan kawat arde ke Ground Rod dengan menggunakan klem arde.
10. Periksa hasil pekerjaan dan yakinkan bahwa jaringan personil dan peralatan dalam keadaan aman.
11. Lapor ke Posko bahwa pekerjaan pemeliharaan telah selesai. 12. Bereskan peralatan kerja & K-3 dan rambu peringatan untuk publik serta
bersihkan areal pekerjaan. 13. Buat Laporan dan Berita Acara pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan
sistem pentanahan. 14. Laporan penyelesaian pekerjaan dan Berita Acara diserahkan kepada
Asman Distribusi.
Keterangan :
1. Ground Rod. 2. Klem Pembumian 3. Konduktor Pembumian. 4. Stainless Steel Strap. 5. Pierching Klem. 6. Kawat Netral JTR.
Gambar 4-104. Gambar Konstruksi Sistem Pembumian
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 142
xzPT. PLN ( PERSERO )
DISTRIBUSI ......
SOP MEMELIHARA
INSTALASI GARDU TIANG
Kode Unit : DIS.HAR.024(2).A
Halaman 1/5
1. DATA LOKASI GARDU TRAFO
1.1. Nomor Gardu : ............................................ 1.2. Nomor Tiang : ............................................ 1.3. Lokasi ............................................
2. NILAI TAHANAN PEMBUMIAN (ARDE) 2.1. Nilai Tahanan
Pembumian Sebelum Perbaikan
: ............. Ohm
2.2. Nilai Tahanan
Pembumian Sesudah Perbaikan
: ............. Ohm
2.3. Nilai Tahanan
Pembumian Setelah Penambahan/Metode Lainnya
:
............. Ohm
3. CATATAN 3.1. ................................................................................................ 3.2. ................................................................................................
Surabaya, ..............................
ASMAN DISTRIBUSI PETUGAS,
( .........................................) ( .........................................)
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 143
4-4 Memasang Saluran Kabel Tanah Tegangan Rendah 4-4-1 Pengecekan Pekerjaan Penarikan Kabel
Sebelum melaksanakan pekerjaan penarikan kabel, maka perlu diadakan pengecekan secara menyeluruh apakah semua hal yang terkait dengan pekerjaan penarikan kabel sudah dipersiapkan dengan baik. Untuk pengecekan pekerjaan penarikan kabel dapat diikuti acuan berikut:
No. Kontrak ....................... Daerah ........................ No. Tag.................... Gbr. Referensi............................................................Uraian.....................
No. Item yang di cek Instalasi OK, Tanda tangan & Tgl.
1. Cocokan Haspel kabel sesuai dengan peruntukan dan rencana pemotongan
2. Cocokan tegangan kabel, temperatur kabel minimum.
3. Cek daftar penarikan kabel untuk arah putaran dan metode penarikan dalam konduit untuk kabel tegangan rendah.
4. Cek arah panah pada haspel kabel untuk keperluan penarikan kabel.
5. Periksa kabel apakah ada kerusakan pada bagian luar.
6. Bagian logam dari kabel yang masih tergulung di dalam haspel kabel di megger sebelum dipasang.
7. Dilakukan cek kontinyuitas dan isolasi pada kabel instrumen sebelum kabel dikeluarkan dari haspel (m, 250 Volt).
8. Dilakukan pengukuran dengan megger terhadap kabel daya dan kontrol yang telah digelar dan dicatat pada Field test Record.
9. Dilakukan cek kontinyuitas dan isolasi untuk kabel instrumen setelah digelar dan dicatat pada Field test Record.
10. Dilakukan High Potential Cable Test (jika diperlukan) dan dicatat dalam Field test Record.
11. Konduktor diidentifikasi apakah sesuai dengan spesifikasi dan gambar.
12. Kabel diberi end seal setelah dipotong. Catatan:
Air dan kotoran yang ada di dalam konduit dibersihkan sebelumdilakukan penarikan kabel kedalamnya.
Keterangan:
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 144
4-4-2 Penempatan Kabel pada Galian tanah Gambar 4-105 sampai dengan 4-134 menunjukkan ukuran lebar dan
kedalaman galian dan persyaratan lain berkaitan dengan pekerjaan penanaman kabel tanah.
Gambar 4-106. Perletakan 2 kabel tanah TR tiap 1 meter di bawah berm
Catatan: - Ukuran dalam mm - Setiap 30 cm tanah urug dipadatkan dengan stamper
Gambar 4-105. Perletakan 1 kabel tanah TR tiap 1 meter di bawah berm
Catatan: - Ukuran dalam mm - Setiap 30 cm tanah urug dipadatkan dengan stamper
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 145
Gambar 4-107. Perletakan 3 kabel tanahTR tiap 1 meter di bawah berm
Catatan: - Ukuran dalam mm - Setiap 30 cm tanah urug dipadatkan dengan stamper
Catatan: - Ukuran dalam mm - Setiap 30 cm tanah urug dipadatkan dengan stamper
Gambar 4-108. Perletakan 4 kabel tanah TR tiap 1 meter di bawah berm
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 146
Gambar 4-109. Perletakan 5 kabel tanah TR tiap 1 meter di bawah berm
Catatan: - Ukuran dalam mm - Setiap 30 cm tanah urug dipadatkan dengan stamper
Catatan: - Ukuran dalam mm - Setiap 30 cm tanah urug dipadatkan dengan stamper
Gambar 4-110. Perletakan 6 kabel tanah TR tiap 1 meter di bawah berm
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 147
Gambar 4-112. Perletakan 8 kabel tanah TR tiap 1 meter di bawah berm
Catatan: - Ukuran dalam mm - Setiap 30 cm tanah urug
dipadatkan dengan stamper
Gambar 4-111. Perletakan 7 kabel tanah TR tiap 1 meter di bawah berm
Catatan: - Ukuran dalam mm - Setiap 30 cm tanah urug
dipadatkan dengan stamper
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 148
Gambar 4-113. Perletakan 1 kabel tanah TR tiap 1 meter di bawah
berm posisi penyebrangan
Catatan: - Ukuran dalam mm - Setiap 30 cm tanah urug dipadatkan dengan stamper - D > 20 cm - D > 50 cm untuk pipa gas
Catatan: - Ukuran dalam mm - Setiap 30 cm tanah urug dipadatkan dengan stamper - D > 20 cm
- D > 50 cm untuk pipa gas Gambar 4-114. Perletakan 1 kabel
tanah TR tiap 1 meter di bawah berm posisi paralel
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 149
Gambar 4-116. Perletakan 2 kabel tanah TR tiap 1 meter di bawah trotoar
Catatan: - Ukuran dalam mm - Setiap 30 Cm tanah urug dipadatkan dengan stamper
Catatan: - Ukuran dalam mm - Setiap 30 Cm tanah urug dipadatkan dengan stamper
Gambar 4-115. Perletakan 1 kabel tanah TR tiap 1 meter di bawah trotoar
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 150
Gambar 4-117. Perletakan 3 kabel tanah TR tiap 1 meter di bawah trotoar
Catatan: - Ukuran dalam mm - Setiap 30 Cm tanah urug dipadatkan dengan stamper
Gambar 4-118. Perletakan 4 kabel tanah TR tiap 1 meter di bawah trotoar
Catatan: - Ukuran dalam mm - Setiap 30 Cm tanah urug dipadatkan dengan stamper
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 151
Gambar 4-119. Perletakan 5 kabel tanah TR tiap 1 meter di bawah trotoar
Catatan: - Ukuran dalam mm - Setiap 30 Cm tanah urug dipadatkan dengan stamper
Gambar 4-120. Perletakan 6 kabel tanah TR tiap 1 meter di bawah trotoar
Catatan: - Ukuran dalam mm - Setiap 30 Cm tanah urug dipadatkan dengan stamper
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 152
Catatan: - Ukuran dalam mm - Setiap 30 Cm tanah urug dipadatkan dengan stamper
Gambar 4-121. Perletakan 7 kabel tanah TR tiap 1 meter di bawah trotoar
Gambar 4-122. Perletakan 8 kabel tanah TR tiap 1 meter di bawah trotoar
Catatan: - Ukuran dalam mm - Setiap 30 Cm tanah urug dipadatkan dengan stamper
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 153
Gambar 4-123. Perletakan 1 kabel tanah TR tiap 1 meter di bawah
trotoar posisi penyebrangan
Catatan: - Ukuran dalam mm - Setiap 30 Cm tanah urug dipadatkan dengan stamper
- D > 20 cm - D > 50 cm untuk pipa gas
Catatan: - Ukuran dalam mm - Setiap 30 Cm tanah urug dipadatkan dengan stamper
- D > 20 cm - D > 50 cm untuk pipa gas
Gambar 4-124. Perletakan 1 kabel tanah TR tiap 1 meter di bawah
trotoar posisi peralel
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 154
Gambar 4-125. Perletakan 1 kabel tanah TR tiap 1 meter melintang
jalan raya aspal (digali)
Catatan: - Ukuran dalam mm - Setiap 30 Cm tanah urug dipadatkan dengan stamper
Catatan: - Ukuran dalam mm - Setiap 30 Cm tanah urug dipadatkan dengan stamper
Gambar 4-126. Perletakan 2 kabel tanah TR tiap 1 meter melintang jalan raya aspal (digali)
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 155
Catatan: - Ukuran dalam mm - Setiap 30 Cm tanah urug dipadatkan dengan stamper
Gambar 4-127. Perletakan 3 kabel tanah TR tiap 1 meter
melintang jalan raya aspal (digali)
Catatan: - Ukuran dalam mm - Setiap 30 Cm tanah urug dipadatkan dengan stamper
Gambar 4-128. Perletakan 4 kabel tanah TR tiap 1 meter melintang jalan raya aspal (digali)
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 156
Gambar 4-129. Perletakan 5 kabel tanah TR tiap 1 meter melintang
jalan raya aspal (digali)
Catatan: - Ukuran dalam mm - Setiap 30 Cm tanah urug dipadatkan dengan stamper
Catatan: - Ukuran dalam mm - Setiap 30 Cm tanah urug dipadatkan dengan stamper
Gambar 4-130. Perletakan 6 kabel tanah TR tiap 1 meter melintang
jalan raya aspal (digali)
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 157
Catatan: - Ukuran dalam mm - Setiap 30 Cm tanah urug dipadatkan dengan stamper
Gambar 4-131. Perletakan 7 kabel tanah TR tiap 1 meter melintang
jalan raya aspal (digali)
Catatan: - Ukuran dalam mm - Setiap 30 Cm tanah urug dipadatkan dengan stamper
Gambar 4-132. Perletakan 8 kabel tanah TR tiap 1 meter melintang
jalan raya aspal (digali)
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 158
Catatan: Ukuran dalam mm Setiap 30 Cm tanah urug
Dipadatkan dengan stamper Kabel dimasukkan kedalam
pipa PNV ∅ 6” jenis AW tebal 6 mm Untuk kabel tanpa armorrod,
dimasukkan ke pipa besi di galvanis 7 micron ∅ 6”. D > 20 cm D > 50 cm untuk pipa gas
Gambar 4-133. Perletakan 1 kabel tanah TR tiap 1 meter melintang jalan raya aspal (digali) posisi penyebrangan
Gambar 4-134. Perletakan 1 kabel tanah TR tiap 1
meter melintang jalan raya aspal (digali) posisi paralel
Catatan: Ukuran dalam mm Setiap 30 Cm tanah urug
Dipadatkan dengan stamper Kabel dimasukkan kedalam
pipa PNV ∅ 6” jenis AW tebal 6 mm Untuk kabel tanpa armorrod,
dimasukkan ke pipa besi di galvanis 7 micron ∅ 6”. D > 20 cm D > 50 cm untuk pipa gas
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 159
Jika kabel tanah dilindungi dengan pipa beton digunakan acuan sebagai berikut:
Tabel 4-6. Ukuran galian tanah untuk beberapa pipa beton
No. Tabung beton φ 20 Cm L D 1. 1 Tabung 100 1000 2. 2 Tabung 100 1000 3. 3 Tabung 900 1000 4. 4 Tabung 1.200 1000 5. 5 Tabung 1.500 1000 6. 6 Tabung 1.800 1000
Gambar 4-138.Ukuran dan penempatan untuk satu kabel dan dua kabel
Gambar 4-135.Susunan struktur
penanaman kabel tanah
Gambar 4-136 Pemasangan kabel tanah
dengan pipa pelindung
Gambar 4-137. Cara meletakkan kabel
tanah di dalam tanah galian
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 160
4-5 Sambungan Pelayanan
4-5-1 Ketentuan Umum Sambungan Pelayanan
Ketentuan umum yang perlu diperhatikan dalam sambungan pelayanan pelanggan, antara lain adalah jarak aman saluran kabel, jumlah pelanggan pada setiap sambungan luar pelanggan (SLP). Batasan-batasan tersebut dapat dilihat pada Gambar 5-139.
Gambar 4-139. Ketentuan umum sambungan pelanggan
Keterangan : JTR = STR s/d APP (STR + SLP + SMP + APP) SP = SLP s/d APP (SLP + SMP + APP) SR = SLP s/d SMP (SLP + SMP) L = 30 m u/ Kabel isolasi dipilin (LVTC) 45 m u/ Kabel jenis Dx/Qx T = 6 m Melintasi Simpang Jalan Umum 5,5 m Melintasi Rel Kereta Api 5 m Melintasi Jalan Umum 4 m Tidak melintasi Jalan Umum
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 161
Gambar 4-140 Ketentuan umum sambungan luar pelanggan
Ketentuan-ketentuan Sambungan Pelayanan.
1. Dari satu tiang boleh dipasang maksimum 5 SLP.
2. Dari SLP 1 boleh disambung berturut-turut (seri) maksimum 5 pelanggan dan tetap memperhatikan beban dan susut tegangan.
3. Jarak sambungan dari tiang ke rumah atau dari rumah ke rumah maksimum 30 meter u/ SLP jenis twisted dan maksimum 45 meter u/ SLP jenis DX/QX.
4. Jarak sambungan dari tiang ke rumah terakhir maksimum 150 meter dan tetap memperhatikan susut tegangan yang diijinkan.
5. Susut tegangan sepanjang SR yang diijinkan maksimum 2% bila SLP disambung pada STR, maksimum 10% bila SLP disambung pada Gardu Trafo/Peti TR.
6. Pada satu tiang atap boleh dipasang maksimum 3 SLP.
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 162
4-5-2 Konstruksi Sambungan Luar Pelayanan (SLP)
Kode M a t e r i a l J U M L A H SKA 11-C SKC 11-C SKA 11-C-T SKC 11-C-T
Vb aa as s bn atp psc p p-1
Pole band double rack Eye nut 5/8” Service swinging clevis Spool insulator ansi 53-1 Clamp loop dead end Armor tape Plastic strap for clamping Bare connector bimetal Protective cap tap connector
1 1 1 1 1
0,5 1 2 -
1 1 1 1 1
0,5 1 4 -
1 1 1 1 1
0,5 1 - 2
1 1 1 1 1
0,5 1 - 4
Gambar 4-141 Konstruksi SLP 1 phasa jenis DX/ 3 phasa jenis QX pada STR tanpa isolasi dan berisolasi
Kode M a t e r i a l J U M L A H SKA 14-C SKC 14-C SKA 14-C-T SKC 14-C-T
Vb da s bn atp psc p p-1
Pole band double rack Bracket secondery Spool insulator ansi 53-1 Clamp loop dead end Armor tape Plastic strap for clamping Bare connector bimetal Protective cap tap connector
1 1 1 1
0,5 1 2 -
1 1 1 1
0,5 1 4 -
1 1 1 1
0,5 1 - 2
1 1 1 1
0,5 1 - 4
Gambar 4-142. Konstruksi SLP 1 phasa jenis DX/ 3 phasa jenis QX pada STR tanpa isolasi dan STR berisolasi
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 163
Kode M a t e r i a l J U M L A H SKA-C SKC-C SKA-C-T SKC-C-T
Vb aa dt psc p p-1
Pole band double rack Eye nut 5/8” Service alum. dead end clamping Plastic strap for clamping Bare connector bimetal Protective cap tap connector
1 1 1 1 2 -
1 1 1 1 4 -
1 1 1 1 - 2
1 1 1 1 - 4
Gambar 4-143 Konstruksi SLP 1 phasa jenis DX/ 3 phasa jenis QX pada STR tanpa isolasi dan STR berisolasi
Kode M a t e r i a l J U M L A H SKA-C1 SKC-C1 SKA-C1-T SKC-C1-T
Vb v-1 dt psc p p-1
Pole band double rack Pole attachment fitting Service alum. dead end clamping Plastic strap for clamping Bare connector bimetal Protective cap tap connector
1 1 1 1 2 -
1 1 1 1 4 -
1 1 1 1 - 2
1 1 1 1 - 4
Gambar 4-144 Konstruksi SLP 1 phasa jenis DX/ 3 phasa jenis QX pada STR tanpa isolasi dan berisolasi
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 164
Kode M a t e r i a l J U M L A H SKA-C2 SKC-C2 SKA-C2-T SKC-C2-T
v-1 dt psc p p-1 sst stp
Pole attachment fitting Service alum. dead end clamping Plastic strap for clamping Bare connector bimetal Protective cap tap connector Stanless steel strap Stoping bucle for sst
1 1 1 2 -
1,75 1
1 1 1 4 -
1,75 1
1 1 1 - 2
1,75 1
1 1 1 - 4
1,75 1
Gambar 4-145 Konstruksi SLP 1 phasa jenis DX/ 3 phasa jenis QX pada STR tanpa isolasi dan berisolasi
Kode M a t e r i a l J U M L A H SKA-T SKC-T SKA-T -T SKC-T -T
Vb aa dt-1 psc p p-1
Pole band double rack Eye nut 5/8” Service alum. dead end clamping Plastic strap for clamping Bare connector bimetal Protective cap tap connector
1 1 1 1 2 -
1 1 1 1 4 -
1 1 1 1 - 2
1 1 1 1 - 4
Gambar 4-146 Konstruksi SLP 1 phasa / 3 phasa jenis Twisted pada STR tanpa isolasi dan STR berisolasi
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 165
Kode M a t e r i a l J U M L A H SKA-T1 SKC-T1 SKA-T1 -T SKC-T1 -T
Vb V-1 dt-1 psc p p-1
Pole band double rack Pole attachment fitting Service alum. dead end clamping Plastic strap for clamping Bare connector bimetal Protective cap tap connector
1 1 1 1 2 -
1 1 1 1 4 -
1 1 1 1 - 2
1 1 1 1 - 4
Gambar 4-147 Konstruksi SLP 1 phasa / 3 phasa jenis Twisted pada STR tanpa isolasi dan STR berisolasi
Kode M a t e r i a l J U M L A H SKA-T2 SKC-T2 SKA-T2 -T SKC-T2 -T
V-1 dt-1 psc p p-1 sst stp
Pole attachment fitting Service alum. dead end clamping Plastic strap for clamping Bare connector bimetal Protective cap tap connector Stanless steel strap Stoping bucle for sst
1 1 1 2 -
1,75 1
1 1 1 4 -
1,75 1
1 1 1 - 2
1,75 1
1 1 1 - 4
1,75 1
Gambar 4-148 Konstruksi SLP 1 phasa / 3 phasa jenis Twisted pada STR tanpa isolasi dan STR berisolasi
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 166
PKA – CPKC - C
Kode M a t e r i a l J U M L A H SKA-T2 SKC-T2 SKA-T2 -T SKC-T2 -T
dr Sdf as s bn atp psc p
Clevis service conduitService dead end fitting Service swmping clevis Spool insulator ansi 53-1 Clamp loop dead end Armor tape Plastic strap for clamping Bare connector bimetal
1- - 1 1
0,5 1 2
1- - 1 1
0,5 1 4
-1 1 1 1
0,5 1 2
- 1 1 1 1
0,5 1 4
Gambar 4-149 Konstruksi SLP 1 phasa jenis DX/ 3 phasa jenis QX pada tiang atap
Gambar 4-150 Konstruksi SLP 1 phasa jenis DX/ 3 phasa jenis QX pada titik tumpu dinding/tiang kayu
PKA 16 – CPKC 16 - C
Kode M a t e r i a l J U M L A H KA10-C KC10-C KA10-C1 KC10 –C1
bt aq as s bn atp psc p
Wire holder clevis screwEye Screw ½ “ x 4” Service swinging clevis Spool insulator ansi 53-1 Clamp loop dead end Armor tape Plastic strap for clamping Bare connector bimetal
1- - 1 1
0,5 1 2
1- - 1 1
0,5 1 4
-1 1 1 1
0,5 1 2
- 1 1 1 1
0,5 1 4
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 167
Kode M a t e r i a l J U M L A H KA-C KC-C CKA-C CKC –C
Sdt j as c ek s bn atp psc p - cpt
Service dead end fittingLag screw 3/8” x 2 1/2 “ Service swinging clevis Bolt machine 5/8” x 6” Locknut 5/8” Spool insulator ansi 53-1 Clamp loop dead end Armor tape Plastic strap for clamping Bare connector bimetal Pasir kali + batu kerikil Cement portland
12 1 - - 1 1
0,5 1 2 - -
12 1 - - 1 1
0,5 1 4 - -
1- 1 1 2 1 1
0,5 1 2
0,02 1
1 - 1 1 2 1 1
0,5 1 4
0,02 1
Gambar 4-151 Konstruksi SLP 1 phasa jenis DX/ 3 phasa jenis QX pada titik tumpu dinding/tiang beton
Kode M a t e r i a l J U M L A H CKA-C1 CKC-C1 CKA-C2 CKC –C2
as o d ek s bn atp psc p - cpt
Service swinging clevis Bolt machine 5/8” x 6” Washer square 2 ¼” Locknut 5/8” Spool insulator ansi 53-1 Clamp loop dead end Armor tape Plastic strap for clamping Bare connector bimetal Pasir kali + batu kerikil Cement portland
1 1 1 1 1 1
0,5 1 2
0,02 1
1 1 1 1 1 1
0,5 1 4
0,02 1
1 1 1 1 1 1
0,5 1 2
0,02 1
1 1 1 1 1 1
0,5 1 4
0,02 1
Gambar 4-152 Konstruksi SLP 1 phasa jenis DX/ 3 phasa jenis QX pada titik tumpu dinding/tiang kayu dan beton
KA - C KC - C
CKA – C CKC – C
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 168
Kode M a t e r i a l J U M L A H CKA-C1 CKC-C1 CKA-C2 CKC –C2
sst stp Sdt v-1 dt-1 psc
Stansless steel strap Stoping bucle for sst Service dead end fitting Pole attachment fitting Service alum. dead end clamping Plastic strap for clamping
- - 1 - 1 1
- - 1 - 1 1
0,35 1 - 1 1 1
0,35 1 - 1 1 1
Gambar 4-153 Konstruksi SLP 1 phasa, 3 phasa Jenis twisted pada tiang atap
Gambar 4-154 Konstruksi SLP 1 phasa, 3 phasa jenis twisted pada titik tumpu dinding/tiang kayu dan beton
Kode M a t e r i a l J U M L A H KA-T KC-T CKA-T CKC–T
Sdt j c ek dt-1 psc - cpt
Service dead end fitting Lag screw 3/8” x 2 1/2 “ Bolt machine 5/8” x 6” Locknut 5/8” Service insul. dead end clamp. Plastic strap for clamping Pasir kali + batu kerikil Cement portland
1 2 - - 1 1 - -
1 2 - - 1 1 - -
1 - 1 2 1 1
0,02 1
1 - 1 2 1 1
0,02 1
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 169
Kode M a t e r i a l J U M L A H KA-T1 KC-T1 CKA-T2 CKC–T2
aq j v-1 dt-1 psc
Eye screw ½” x 4” Lag screw ½” x 4” Pole attachment fitting Service insul. dead end clamp. Plastic strap for clamping
1 - - 1 1
1 - - 1 1
- 1 1 1 1
- 1 1 1 1
Gambar 4-155 Konstruksi SLP 1 phasa, 3 phasa jenis twisted pada titik tumpu dinding/tiang kayu
Kode M a t e r i a l J U M L A H CKA-T1 CKC-T1 CKA-T2 CKC–T2
C d ek v-1 dt-1 psc
- cpt
Bolt machine 5/8” x Panjang disesuaikan Washer square 2 ¼” Locknut 5/8” Pole attachment fitting Service insul. dead end clamp. Plastic strap for clamping Pasir kali + batu kerikil Cement portland
1 1 1 1 1 1
0,02 1
1 1 1 1 1 1
0,02 1
1 1 1 1 1 1
0,02 1
1 1 1 1 1 1
0,02 1
Gambar 4-156 Konstruksi SLP 1 phasa, 3 phasa jenis twisted pada titik tumpu dinding/tiang kayu
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 170
4-5-3 Penggunaan Pipa Instalasi.
Jika menggunakan pipa instalasi dengan bahan logam harus dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:
a. Sambungan-sambungan harus kontak langsung dan bebas isolasi. b. Ujung pipa bagian atas dihubung pada pangkal tiang atap dengan kawat
tembaga minimum 6 mm2 dan dilas/disolder. c. Ujung pipa bagian bawah dihubungkan ke kawat pentanahan pada peti
tegangan rendah. Tabel 4-7. Daftar material konstruksi SMP dengan tiang atap dan titik tumpu
untuk SR 1 phasa/3 phasa dengan SLP jenis DX/QX dan SMP jenis NYM/NYY.
4-5-4 Konstruksi Sambungan Masuk Pelanggan (SMP) Gambar berikut menunjukkan beberapa jenis Sambungan Masuk
Pelanggan (SMP) melalui kerangka tiang atap dan atau tidak melalui tiang atap.
Kode M a t e r i a l J U M L A H
PMA8-CPMA8-C1
PMC8-C PMC8-C1
MA8-C CMA8-C
MC8-C CMC8-C
gc ptc gd gd-1 j gc-1 lbp shp gd-2 cv cv cv-1 cv-1 slp gd-3
Service must 11/2 “ x 1 ½” M Protective cap for gc 11/2” Fixing colar 11/2” Fixing ring 11/2” Lag screw 3/8” x 2” Union/PVC pipe, conduit Union/PVC L bouw pipe Union/PVC shock pipe Staples conduit pipe and nail Service cable intrance NYM 2c Service cable intrance NYM 4c Service cable external DX type Service cable external QX typeSheet lead pipe, 1 ½” hole Strap for sheet lead 11/2”
1 1 1 1 3
9*) 3*) 1*)
16*) 10*)
- 45*)
- 1 1
1 1 1 1 3
9*) 3*) 1*)
16*) -
10*) -
45*) 1 1
- - - - -
10*) 5*) 1*)
20*) 10*)
- 45*)
- - -
- - - - -
10*) 5*) 1*)
20*) -
10*) -
45*) - -
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 171
Gambar 4-158 Konstruksi SMP dengan tiang atap untuk SR 1 phasa/3 phasa dengan SLP jenis DX/QX dan SMP jenis NYM/NYY di luar plapon
Gambar 4-157 Konstruksi SMP dengan tiang atap untuk SR 1 phasa/3 phasa dengan SLP jenis DX/QX dan SMP jenis NYM/NYY di luar bangunan.
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 172
Gambar 4-159 Konstruksi SMP dengantitik tumpu untuk SR 1 phasa/3 phasa dengan SLP jenis DX/QX dan SMP jenis NYM/NYY di luar bangunan.
Gambar 4-160 Konstruksi SMP dengan titik tumpu untuk SR 1 phasa/3 phasa dengan SLP jenis DX/QX dan SMP jenis NYM/NYY di luar bangunan.
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 173
Tabel 4-8 Daftar material konstruksi SMP dengan tiang atap/titik tumpu untuk SR 1 phasa/3 phasa tanpa sambungan jenis Twisted
Kode M a t e r i a l J U M L A H
PMA8-TPMA8-T1
PMC8-T PMC8-T1
MA8-T CMA8-T
MC8-T CMC8-T
gc ptc gd gd-1 j gc-1 lbp shp gd-2 cv cv slp gd-3
Service must 11/2 “ x 1 ½” M Protective cap for gc 11/2” Fixing colar 11/2” Fixing ring 11/2” Lag screw 3/8” x 2” Union/PVC pipe, conduit Union/PVC L bouw pipe Union/PVC shock pipe Staples conduit pipe and nail Intrance and external service cable, include LVTC type 2 core Intrance and external service cable, include LVTC type 4 core Sheet lead pipe, 1 ½” hole Strap for sheet lead 11/2”
1 1 1 1 3
9*) 3*) 1*) 16*)
40*)
- 1 1
1 1 1 1 3
9*) 3*) 1*)
16*)
40*) - 1 1
- - - - -
10*) 5*) 1*) 20*)
-
40)* - -
- - - - -
10*) 5*) 1*) 20*)
-
40*) - -
Gambar 4-161 Konstruksi SMP dengan tiang atap untuk SR 1 phasa/3 phasa tanpa sambungan jenis Twisted
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 174
Gambar 4-162 Konstruksi SMP dengan tiang atap untuk SR 1 phasa/3 phasa tanpa sambungan jenis Twisted
Gambar 4-163 Konstruksi SMP dengan tiang atap untuk SR 1 phasa/3 phasa tanpa sambungan jenis Twisted
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 175
Gambar 4-165 Pemasangan APP pelanggan TR 1 phasa/3 phasa dengan OK type I/III pada dinding yang telah ada pelindungnya
Gambar 4-164 Konstruksi SMP dengan titik tumpu untuk SR 1 phasa/3 phasa tanpa sambungan jenis Twisted.
KODE M A T E R I A L JUMLAH 1 FASA 3 FASA
go go
APP 3 fasa dengan OK type III APP 3 fasa dengan OK type I
1
1
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 176
KODE MATERIAL JUMLAH go - - - - - - - - -
APP 1 fasa dengan OK type I Asbes gelombang 1000 x 550 Segitiga penyangga 200 x 200 x 280 dengan besi L 50 x 50 x 5 Kayu 40 x60 x 900 Fisher 3/8” Paku sekrup 3/8” x 2” Mur – baut 3/8” x 31/2 ” Paku payung Pasir (kubik) Semen (kg)
1 1
2 2 4 4 4 6
0,01 2
Gambar 4-166 Pemasangan APP pelanggan TR 1 phasa dengan OK type I dengan pelindung tambahan.
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 177
Gambar 4-167 Pemasangan APP pelanggan TR 3 phasa dengan OK type III dengan pelindung tambahan.
KODE MATERIAL JUMLAHgo - - - - - - - - -
APP 3 fasa dengan OK type III Asbes gelombang 1400 x 900 Segitiga penyangga 400 x 400 x 560 dengan besi L 50 x 50 x 5 Kayu 40 x60 x 900 Fisher 3/8” Paku sekrup 3/8” x 2” Mur – baut 3/8” x 31/2 ” Paku payung Pasir (kubik) Semen (kg)
1 1
2 2 4 4 4 6
0,01 3
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 178
KODE MATERIAL JUMLAH go gc - - -
vo - - v
dl 1 dl 1
-
APP 3 fasa dengan OK type VI khusus pasangan luar Gas pipe disesuaikan Knie disesuaikan Besi kanal C np 6 Besi kanal C np 6 250 mm Pole band Mur – baut 3/8” x 11/2 ” Mur – baut 1/2” x 11/2 ” Beugel disesuaikan Pipe spacer ¾” x 3/8” Pipe spacer ¾” x 7/8” Seal tap (rol)
1 1 4 2 2 4 4 8 4 1 1 2
Gambar 4-168 Pemasangan APP pelanggan TR 3 phasa pada Gardu Trafo Tiang.
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 179
4-6 Gangguan pada Saluran Udara Tegangan Rendah 4-6-1 Gangguan Hilang Pembangkit
Dalam beroperasi, pembangkit tenaga listrik tidak bisa dipisahkan dari sub sistem tenaga listrik yang lain yaitu penyaluran (transmisi), distribusi dan pelelangan, karena pembangkit tenaga listrik merupakan salah satu sub sistem dari sistem tenaga listrik.
Suatu sistem tenaga listrik yang sangat luas cakupan areanya, menyebabkan timbulnya gangguan tidak bisa dihindari. Salah satu sub sistem yang kemungkinan mengalami gangguan, adalah pembangkit tenaga listrik. Bentuk gangguan tersebut adalah hilangnya daya atau pasokan daya pada pembangkit atau biasa disebut hilangnya pembangkit.
Secara garis besar, gangguan hilangnya pembangkit diakibatkan oleh dua hal, yaitu yang bersifat internal dan gangguan yang bersifat ekstemal.
1) Gangguan internal yaitu yang diakibatkan oleh pembangkit itu sendiri, misalnya: kerusakan/gangguan pada penggerak mula (prime over) dan kerusakan/gangguan pada generator, atau komponen lain yang ada di pembangkitan.
2) Gangguan eksternal, yaitu gangguan yang berasal dan diakibatkan dari luar pembangkitan, misalnya: gangguan hubung singkat pada jaringan. Hal ini akan menyebabkan sistem proteksi (relai atau circuit breaker) bekerja dan memisahkan suatu pembangkitan dari sistem yang lainnya. Apabila tingkat kemampuan pembebanan pembangkitan yang hilang atau terlepas dari sistem tersebut melampaui spinning reserve sistem, maka terjadi penurunan frekuensi terus menerus. Hal ini harus segera diatasi, karena akan menyebabkan trip pada unit pembangkitan yang lain, sehingga berakibat lebih fatal, yaitu sistem akan mengalami padam total (collapse).
4-6-2 Gangguan Beban Lebih
Dalam suatu sistem tenaga listrik, yang dimaksud gangguan beban lebih adalah pelayanan kepada pelanggan listrik yang melebihi kemampuan sistem tenaga listrik yang ada, misal: trafo distribusi dengan kapasitas daya terpasang 100 KVA, akan tetapi melayani pelanggan lebih besar dari kapasitasnya. Hal ini menyebabkan trafo bekerja pada kondisi abnormal.
Beban lebih akan menyebabkan arus yang mengalir pada jaringan listrik menjadi besar, selanjutnva menimbulkan panas yang berlebihan, yang akhirnya akan menyebabkan umur hidup (life time) peralatan dan material pada jaringan listrik menjadi pendek atau mempercepat proses penuaan dan kerusakan.
4-6-3 Gangguan Hubung Singkat
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 180
Gangguan hubung singkat pada jaringan listrik, dapat terjadi antara phasa dengan phasa (2 phasa atau 3 phasa) dan gangguan antara phasa ke tanah. Timbulnya gangguan bisa bersifat temporer (non persistant) dan gangguan yang bersifat permanent (persistant).
Gangguan yang bersifat temporer, timbulnya gangguan bersifat sementara, sehingga tidak memerlukan tindakan. Gangguan tersebut akan hilang dengan sendirinya dan jaringan listrik akan bekerja normal kembali. Jenis gangguan ini ialah : timbulnya flashover antar penghantar dan tanah (tiang, traverse atau kawat tanah) karena sambaran petir, flashover dengan pohon-pohon, dan lain sebagainya.
Gangguan yang bersifat permanen (persistant), yaitu gangguan yang bersifat tetap. Agar jaringan dapat berfungsi kembali, maka perlu dilaksanakan perbaikan dengan cara menghilangkan gangguan tersebut. Gangguan ini akan menyebabkan terjadinya pemadaman tetap pada jaringan listrik dan pada titik gangguan akan terjadi kerusakan yang permanen. Contoh: menurunnya kemampuan isolasi padat atau minyak trafo. Di sini akan menyebabkan kerusakan permanen pada trafo, sehingga untuk dapat beroperasi kembali harus dilakukan perbaikan.
Beberapa, penyebab yang mengakibatkan terjadinya, gangguan hubung singkat, antara lain:
1) Terjadinya angin kencang, sehingga menimbulkan gesekan pohon dengan jaringan listrik.
2) Kesadaran masyarakat yang kurang, misalnya bermain layang-layang dengan menggunakan benang yang bisa dilalui aliran listrik. Ini sangat berbahaya jika benang tersebut mengenai jaringan listrik.
3) Kualitas peralatan atau material yang kurang baik, misaInya: pada JTR yang memakai Twested Cable dengan mutu yang kurang baik, sehingga isolasinya mempunyai tegangan tembus yang rendah, mudah mengelupas dan tidak tahan panas. Hal ini juga akan menyebabkan hubung singkat antar phasa.
4) Pemasangan jaringan yang kurang baik misalnya: pemasangan konektor pada JTR yang memakai TC, apabila pemasangannya kurang baik akan menyebabkan timbulnya bunga api dan akan menyebabkan kerusakan phasa yang lainnya. Akibatnya akan terjadi hubung singkat.
5) Terjadinya hujan, adanya sambaran petir, karena terkena galian (kabel tanah), umur jaringan (kabeI tanah) sudah tua yang mengakibatkan pengelupasan isolasi dan menyebabkan hubung singkat dan sebagainya.
4-6-4 Gangguan Tegangan Lebih
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 181
Yang dimaksud gangguan tegangan lebih ialah, besarnya tegangan yang ada pada jaringan listrik melebihi tegangan nominal, yang diakibatkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
1) Adanya penurunan beban atau hilangnya beban pada jaringan, yang disebabkan oleh switching karena gangguan atau disebabkan karena manuver.
2) Terjadinya gangguan pada pengatur tegangan otomatis/automatic voltage regulator (AVR) pada generator atau pada on load tap chenger transformer.
3) Putaran yang sangat cepat (over speed) pada generator yang diakibatkan karena kehilangan beban.
4) Terjadinya sambaran petir atau surja petir (lightning surge), yang mengakibatkan hubung singkat dan tegangan lebih.
5) Terjadinya surja hubung (switch surge), yaitu berupa hubung singkat akibat bekerjanya circuit breaker, sehingga menimbulkan tegangan transient yang tinggi. Hal ini sering terjadi pada sistem jaringan tegangan ekstra tinggi.
Gangguan tegangan lebih akan merusak isolasi, dan akibatnya akan merusak peralatan karena insulation break down (hubung singkat) atau setidak-tidaknya akan mempercepat proses penuaan peralatan dan memperpendek umur peralatan.
Sebenarnya kondisi abnormal ini kurang tepat jika disebut sebagai gangguan. Akan tetapi kondisi abnormal ini jika berlangsung terus menerus akan menyebabkan peralatan cepat rusak, umur peralatan pendek dan membahayakan sistem.
Sebenamya timbulnya gangguan beban lebih ini, khususnya terhadap pasok daya ke pelanggan, bisa dieliminir oleh pihak PLN dengan cara: pembebanan pada tiap-tiap trafo harus diinventarisir dan dimonitor dengan seksama, sehingga pembebanannya tidak melebihi kapasitas trafo.
Beberapa penyebab yang mengakibatkan timbulnya gangguan beban lebih ialah:
1) Semakin meningkatnya permintaan energi listrik dari pelangggan, sehingga memaksa trafo dan saluran dengan beban maksimum, bahkan mungkin lebih besar dari kemampuannya. Hal ini disebabkan:
a. Jumlah volume jaringan listrik yang terbatas dan kurang bisa mengimbangi jumlah pelanggan.
b. Kurangnya pengertian dan ketidaktahuan masyarakat pelanggan listrik terhadap masaIah kelistrikan. Contoh: pada suatu daerah tertentu terdapat sambungan listrik ke pelanggan dengan kondisi beban trafo dan jaringan yang telah maksimum. Ada calon pelanggan lain yang berdekatan dengan pelanggan PLN tersebut, ngotot untuk bisa disambungkan aliran listrik ke rumahnya. Akhirnya dengan sangat terpaksa PLN melayani,
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 182
sehingga beban trafo dan jaringan di daerah tersebut menjadi lebih (over load).
c. Terjadinya loses daya pada jaringan dan trafo, yang diakibatkan oleh berbagai hal, sehingga trafo beserta jaringannya tidak bisa bekerja pada beban penuh.
2) Adanya manuver atau perubahan aliran beban di jaringan, setelah timbulnya gangguan.
3) Adanya pemakaian energi listrik yang di luar kontrol dan catatan PLN atau tanpa sepengetahuan PLN, sehingga PLN sulit mendeteksi beban trafo dan jaringan yang ada. Hal ini akan menyebabkan timbulnya gangguan beban lebih.
4-6-5 Gangguan Instabilitas
Yang dimaksud gangguan instabilitas adalah gangguan ketidakstabilan pada sistem (jaringan) listrik. Gangguan ini diakibatkan adanya hubung singkat dan kehilangan pembangkit, yang selanjutnya akan menimbulkan ayunan daya (power swing).
Efek yang lebih besar akibat adanya ayunan daya ini adalah, mengganggu sistem interkoneksi jaringan dan menyebabkan unit-unit pembangkit lepas sinkron (out of synchronism), sehingga relai pengaman salah kerja dan menyebabkan timbulnya gangguan yang lebih luas.
Untuk mengantisipasi agar gangguan instabilitas tidak teijadi, ada beberapa cara yaitu: konstruksi jaringan harus baik, sistem proteksi harus andal, pengoperasian dan pemeliharaan harus baik dan benar, dan sebagainya.
4-6-6 Gangguan karena konstruksi jaringan yang kurang baik
Yang dimaksud sistem jaringan di sini adalah, mulai dari pembangkitan, penyaluran, distribusi sampai dengan instalasi listrik pelanggan. Sedangkan yang dimaksud gangguan konstruksi jaringan adalah, gangguan yang terjadi akibat kondisi jaringan yang tidak memenuhi ketentuan dan standard teknik.
Di sini ingin ditekankan bahwa sistem jaringan sangat menentukan tingkat keberhasilan dan keandalan sistem tenaga listrik. Beberapa hal yang mengakibatkan gangguan sistem jaringan, adalah:
1) Perencanaan yang kurang baik misalnya: tidak mempertimbangkan keseimbangan antara supply and demand (daya yang tersedia dan kebutuhan beban pelanggan), design konstruksi yang kurang tepat, dan lain sebagainya.
2) Peralatan dan material yang dipasang mempunyai standard teknik yang rendah (under quality).
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 183
3) Pemasangan yang kurang baik, yang diakibatkan kesadaran pelaksana pekerjaan yang rendah dan pengawasan dari pihak Owner yang kurang ketat.
4) Pengoperasian dan pemeliharaan yang kurang baik, kegagalan kerja sistem proteksi (peralatan pengaman) dan penuaan pada, peralatan/material jaringan.
Hal tersebut di atas akan menyebabkan timbulnya berbagai gangguan pada jaringan listrik. Hal ini bisa diatasi sedini mungkin, yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelak-pekerjaan, komisioning, pengoperasian dan pemeliharaan jaringan listrik, harus mengikuti kaidah, ketentuan dan standard teknik yang telah ditentukan.
4-7 Mengatasi Gangguan pada Sistem Tenaga Listrik 4-7-1 Konstruksi Jaringan Listrik yang Baik
Terjadinya gangguan pada sistem tenaga listrik, tidak mungkin dihilangkan dan tidak dapat dihindari sama sekali. Upaya yang bisa kita tempuh adalah mengurangi terjadinya gangguan tersebut.
Mengurangi terjadinya gangguan pada sistem tenaga listrik merupakan upaya yang bersifat represif dan antisipasif, yaitu memasang dan mewujudkan adanya konstruksi jaringan listrik yang baik, dengan cara sebagai berikut:
1) Pada saat perencanaan sistem tenaga listrik, harus ditentukan design yang baik dan penentuan spesifikasi peralatan dan material harus memenuhi ketentuan teknik, sehingga pada saat beroperasi tahan terhadap kondisi kerja normal maupun dalam keadaan terjadi gangguan. Tahan terhadap pengaruh elektris, thermis maupun mekanis atau tidak terjadi overstress elektris dan mekanis, serta tidak terjadi overheated.
2) Material yang akan dipasang harus dapat diandalkan, mempunyai kualitas yang baik, mempunyai persyaratan dan standard teknik, yang dibuktikan dengan type test, sertifikat LMK, SPLN, IEC dan lain sebagainya. Atau berdasarkan pengalaman, peralatan/meterial tersebut telah terbukti keandalannya.
3) Pemasangan peralatan dan material harus dilaksanakan sebaik- baiknya, sesuai dengan design, spesifikasi dan ketentuan dalam. RKS dan kontrak. 4) Pada saat pelaksanaan pekerjaan, harus ada pengawasan dari pihak
PLN, sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan dan ketidak sesuaian dengan RKS dan kontrak, dapat dihindari.
5) Memasang kawat pentanahan (khususnya pada SUTET/SUTT), dengan tahanan pentanahan yang rendah. Untuk keperluan pemeriksaan dan pemeliharaan, konduktor pentanahannya harus bisa dilepas dari kaki tiangnya.
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 184
6) Setelah selesai dibangun dan sebelum dioperasikan, jaringan listrik tersebut harus di test atau dilaksanakan komisioning, terlebih dahulu, sehingga bisa diyakinkan bahwa jaringan tersebut akan dapat beroperasi dengan baik, andal dan aman.
7) Pengopcrasian yang baik, dengan memperhatikan dan melaksanakan: a. Melaksanakan pemeliharaan rutin dan berkala sesuai kebutuhan.
b. Mengadakan pemeriksaan dan perbaikan.
c. Melaksanakan penebangan/pemaprasan ranting dan dahan pohon yang ada di sekitar jaringan SUTET, SUTT, SUTM dan SUTR, yang kemungkinan akan menyebabkan gangguan. Harus diperhitungkan, bahwa pada saat terjadi hembusan angin, dahan-dahan pohon tersebut harus tetap mempunyai jarak yang aman dengan kawat phasa jaringan.
8) Pada jaringan SUTR dan SLJTM, digunakan kawat penghantar (konduktor) yang berisolasi, misalnya: AAAC OC, AAC OC dan Twested Cable.
9) Mengidentifikasi dan menginventarisir penyebab gangguan serta, melakukan penyelidikan, sebagai umpan balik dan masukan di dalam menentukan sistem proteksi yang lebih baik.
4-7-2 Pemasangan Sistem Proteksi yang Andal
Pemasangan peralatan pengaman (sistem proteksi) pada jaringan listrik, bertujuan untuk mengurangi akibat terjadinya gangguan. Hal ini harus dilakukan, karena timbulnya gangguan pada jaringan listrik tidak mungkin dicegah sama sekali. 1) Fungsi peralatan pengaman (proteksi).
Sistem proteksi merupakan kesatuan (gabungan) dari alat-alat (sub sistem) proteksi, berfungsi untuk:
a. Mendeteksi adanya gangguan (kondisi abnormal) pada sistem tenaga listrik yang diamankannya, sehingga tidak menimbulkan kerusakan.
b. Melepaskan atau memisahkan (mengisolasi) bagian sistem yang
terganggu sehingga, tidak meluas ke bagian sistem yang tidak terganggu dan bagian sistem lainnya dapat terus beroperasi.
2) Pertimbangan pemasangan sistem proteksi.
Dalam menentukan dan menetapkan pemasangan sistem proteksi pada jaringan listrik, ada beberapa hal yang dijadikan sebagai pertimbangan, yaitu:
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 185
a. Fungsi peralatan proteksi, yaitu: pemasangan peralatan proteksi pada masing-masing sub sistem jaringan listrik harus tepat, sesuai dengan fungsinya.
b. Area pengamanan, yaitu: pemasangan peralatan pengaman (relay pengaman) pada tiap-tiap sub area (section), dimaksudkan apabila terjadi gangguan pada section tertentu, maka relay dapat mendeteksi gangguan dengan bantuan PMT, melepaskan section yang terganggu dari bagian jaringan (sistem) yang lainnya. Antara section yang satu dengan section lainnya dalam satu sistem tenaga listik, bisa dihubungkan dan diputuskan oleh PMT.
c. Sistem pengaman ganda, yaitu: pemasangan peralatan pengaman ganda. (utama dan cadangan) dengan maksud apabila pengaman utama gagal bekerja, masih ada pengaman lain yang bisa mengamankan sistem dari gangguan. Pengaman cadangan akan bekerja setelah pengaman utama gagal bekerja, sehingga pengaman cadangan bekerja dengan waktu tunda (time delay) untuk memberi kesempatan pengaman utama terlebih dahulu.
d. Kriteria peralatan pengaman yang mehputi:
- Peralatan pengaman harus mempunyai kepekaan (sensitivity) yang tinggi, sehingga cukup peka dalam mendeteksi gangguan di daerah pengamanannya, meskipun gangguan yang timbul hanya memberikan rangsangan yang minim.
- Peralatan pengaman harus mempunyai keandalan (reliability yang tinggi, dengan tingkat kepastian bekerja (dependability) yang bisa diandalkan, dapat mendeteksi dan melepaskan sub sistem yang mengalami gangguan serta tidak boleh gagal bekerja (mempunyai dependality tinggi). Realibility peralatan pengaman juga harus mempunyai tingkat keamanan (security) yang tinggi atau tidak boleh salah keja. Contoh salah kerja ialah : peralatan pengaman mengalami trip, padahal tidak ada gangguan pada jaringan atau gangguan terjadi pada sub are (sub sistem) di luar pengamanan peralatan pengaman tersebut. Hal ini akan merugikan, karena menimbulkan pemadaman aliran listrik, yang sebenamya tidak boleh terjadi.
- Peralatan pengaman harus mempunyai selektivitas (selectivity) yang tinggi, yaitu : harus bisa mengamankan pada sub area (sub sistem) yang di kawasan pengaman utamanya. Relay harus bisa bekerja sesuai kebutuhan, misalnya harus bekerja cepat atau bekerja dengan waktu tunda (tyme delay) atau bahkan tidak harus bekerja, sehingga relay harus bersifat selektif
- Peralatan pengaman harus mempunyai kecepatan (speed) yang tinggi, yaitu dapat memisahkan sub sistem yang terganggu secepat mungkin, sehingga kerusakan akibat gangguan dapat diperkecil.
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 186
4-8 Pengaman terhadap Tegangan Sentuh Jika suatu obyek bertegangan tersentuh oleh tubuh manusia, maka
pada umumnya arus listrik mengalir ke dalam tubuh manusia tersebut. Tetapi sebenarnya yang berbahaya bagi tubuh bukanlah tegangan itu sendiri, melainkan arus listrik yang mengalir ke dalam tubuh manusia, sedangkan tegangan barulah berbahaya apabila akibat sentuhan dengan tegangan itu menyebabkan mengalirnya arus listrik yang cukup besar di dalam tubuh. Jika tidak menyebabkan mengalirnya arus maka tegangan itu tidak berbahaya. Oleh karena itu, sering kita lihat burung-burung bertengger dengan enaknya pada SUTT 70 kV.
Banyak riset yang telah dilakukan terkait dengan akibat arus listrik mengalir ke dalam tubuh. Berdasarkan penelitian yang dilaporkan oleh IEC Report Publication 479 mengemukakan hal-hal sebagai berikut (seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 4-169.)
Daerah (1) Daerah di mana arus tidak menimbulkan reaksi apa-apa
Daerah (2) Daerah di mana arus mungkin sudah terasa, tetapi biasanya tidak menimbulkan akibat pathophsiologis
Daerah (3) Daerah di mana biasanya tidak mengakibatkan bahaya fibrilasi (denyut jantung tak teratur atau berhenti)
Daerah (4) Daerah di mana fibrilasi bisa terjadi dengan kemungkinan sampai 50%
Daerah (5) Daerah di mana fibrilasi bisa terjadi dengan kemungkinan lebih dari 50%.
Jika tegangan tersentuh ke suatu tubuh, dengan kaki menginjak ke tanah, maka akan mengalirlah arus listrik di dalam tubuh yang besarnya tergantung dari tahanan tubuh dan tahanan kontak pada kedua titik sentuhan. Meskipun yang berbahaya bagi tubuh adalah arus sebagai dasar
Gambar 4-169 Pembagian daerah pengaruh arus bolak-balik (pada 50-60 hz) terhadap orang dewasa
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 187
untuk menetapkan persyaratan instalasi listrik adalah lebih praktis jika dinyatakan sebagai tegangan sentuh sebagai fungsi dari waktu. Dalam Standar IEC Publication 364 4-41, 1977 (Amandemen 1) dinyatakan bahwa tegangan sentuh sebagai fungsi dari waktu yang diijinkan (Tabel 4-9).
Tabel 4-9 Tegangan sentuh yang aman sebagai fungsi dari waktu Lama Sentuhan
Maksimum (detik) Besar tegangan sentuh
Arus bolak-balik (V) Arus Searah (V) < 50 < 120
5 50 120 1 75 140
0,5 90 160 0,2 110 175 0,1 150 200
0,05 220 250 0,03 280 310
Bila tubuh tersengat aliran listrik, besar arus yang melewati tubuh bergantung pada tegangan listrik yang mengenainya dan lintasan yang dilalui arus listrik. Besar tahanan tubuh manusia sangat dipengaruhi oleh keadaan kelembaban tubuh dan lintasan tubuh yang dilalui arus dan besar tegangan yang disentuh. Gambar 4-169 memperlihatkan besar tahanan tubuh sebagai fungsi dari tegangan sentuh. Garis e dalam Gambar 4-169 menunjukkan arus yang merupakan hasil bagi tegangan sentuh dengan besar tahanan tubuh yang berkaitan. Ternyata garis e selalu mengambil jarak dengan garis c di sebelah kirinya, hal ini berarti bahwa jika persyaratan seperti dalam Tabel 4-7 itu dipenuhi, maka bahaya fibrilasi dihindari.
Tabel 4-10 Tahanan tubuh sebagai fungsi dari tegangan sentuh Tegangan Sentuh
(V) Tahanan tubuh
(Ohm) 25 2500 50 2000
250 1000 Harga asimtut 650
*) Kurva ini menyatakan tahanan tubuh antara satu tangan dan satu kaki, atau antara tangan kiri dan tangan kanan.
4-8-1 Cara Pengamanan terhadap Tegangan Sentuh Sentuhan dengan tegangan dapat terjadi secara langsung dan tidak
langsung. Pengamanan terhadap sentuhan langsung adalah pengamanan terhadap sentuhan pada bagian yang aktif dari suatu peralatan atau instalasi yang dalam keadaan normalnya bertegangan. Sedangkan pengamanan terhadap sentuhan tidak langsung adalah pengamanan terhadap sentuhan pada “badan” peralatan atau instalasi yang menjadi bertegangan pada waktu ada gangguan atau hubungan singkat ke “badan” itu. Yang dimaksud badan adalah bagian konduktif yang tidak merupakan bagian sirkit.
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 188
Pengamanan terhadap tak langsung disebut pula pengamanan terhadap tegangan sentuh pada waktu ada gangguan.
Secara ringkas cara-cara pengamanan terhadap tegangan sentuh dapat diuraikan sebagai berikut: Pengamanan terhadap tegangan sentuh baik yang langsung maupun yang tidak langsung, mencakup: Tegangan rendah pengaman (PUIL pasal 323) yaitu di bawah 50 V, misalnya 42 V, 24 V, 12 V dan sebagainya, sehingga bila terjadi sentuhan baik yang langsung ataupun tak langsung tidak berbahaya. Tegangan rendah pengamanan dapat diperoleh dengan cara-cara berikut:
a) Dengan trafo pengaman, yaitu yang mempunyai belitan sekunder yang terpisah dari primernya yang didisain khusus sehingga tidak memungkinkan terjadinya hubungan singkat antara belitan primer dan sekunder.
b) Motor-generator set
c) Battery accu dan cell kering
Pengaman terhadap sentuhan langsung mencakup:
a) Pengamanan dengan isolasi pada bagian-bagian yang aktif (PUIL, pasal 310), misalnya kabel, porselin, karet berisolasi dan sebagainya.
b) Pengamanan dengan selungkup atau sekat f (PUIL, pasal 310 B dan C), misalnya kotak saklar, perlengkapan hubung bagi (PHB).
c) Pengamanan dengan penghalang (PUIL, pasal 213), misalnya sekedar dipagari agar orang tidak bisa mendekat, atau meletakkannya dibelakang kisi-kisi.
d) Pengamanan dengan penempatan di luar jangkauan tangan, misalnya bagian yang bertegangan ditempatkan 2,5 m di atas lantai.
e) Pengamanan tambahan dengan Saklar Pengaman Arus ke Tanah (SPAT, earth leakage circuit breaker). Ini hanyalah merupakan pengamanan tambahan (extra) di samping pengamanan-pengamanan lainnya, dimaksudkan untuk mengamankan terhadap sentuhan langsung yang mungkin masih terjadi. Saklar ini bekerja berdasarkan pada adanya arus bocor ke tanah yang disebut juga arus sisa (residual current) yang timbul akibat sentuhan langsung karena arus bocor ke tanah sebagai akibat sentuhan langsung ini sangat kecil, maka saklar inipun harus sangan sensitif, yaitu arusbocor sebesar 30 mA sudah mampu menyebabkan trip-nya saklar.
Pengamanan terhadap sentuhan tak langsung, mencakup:
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 189
a) Pengamanan dengan pemutusan secara otomatis dari suplai, yang memerlukan pengaman dan alat-alat pengaman seperti misalnya sekring dan saklar pengaman.
b) Pengamanan dengan isolasi pengaman (lihat PUIL, pasal 322A.I.a), yaitu dengan cara memberi isolasi tambahan di samping isolasi utamanya (berisolasi ganda), sehingga apabila terjadi kerusakan pada isolasi utamanya, badan peralatan yang mungkin tersentuh tangan itu dengan bahan isolasi, memasang selungkup dari bahan isolasi, atau dapat juga badan peralatan sendiri dari bukan bahan konduktif.
c) Pengamanan dengan alas isolasi (lihat PUIL, pasal 322A), yaitu memberikan isolasi pada tempat kaki berpijak atau pada lantai dan benda-benda konduktif lainnya yang berhubungan dengan tanah yang terjangkau tangan sedemikian sehingga tercegahlah orang terkena tegangan sentuh yang berbahaya bila terjadi kegagalan isolasi.
d) Pengamanan dengan hubungan alas kaki yang konduktif dengan badan atau bagian peralatan yang terpegang dengan tangan sedemikian sehingga tidak ada beda potensial antara alas kaki dan badan/bagian peralatan yang terpegang tangan bila terjadi kegagalan isolasi.
e) Pengamanan dengan pemisah pengaman (electrical separation) (lihat PUIL pasal 329), yaitu dengan memakai generator motor set atau trafo pemisah. Trafo pemisah adalah trafo yang belitan sekundernya terpisah dari belitan primernya dan rangkaian sekundernya, di mana peralatan itu tersambung, tidak diketanahkan sehingga bila terjadi kegagalan isolasi peralatan tercegahlah timbulnya tegangan sentuh yang berbahaya.
4-8-2 Pentanahan Tegangan Rendah Fungsi Pentanahan tegangan rendah untuk menghindari bahaya
tegangan sentuh bila terjadi gangguan atau kegagalan isolasi pada peralatan atau instalasi. Pentanahan netral pada jaringan tegangan rendah adalah yang efektif, di mana menurut persyaratan pentanahan netral harus mempunyai tahanan pentanahan kurang dari 5 Ohm. Ketentuan ini sesuai dengan standar konstruksi PUIL, SPLN 3:1978 bahwa semua jaringan tegangan rendah dan instalasi harus menggunakan sistem Pentanahan Netral Pengaman (PNP), yaitu system pentanahan dengan cara menghubungkan badan peralatan atau instalasi dengan hantaran netral yang ditanahkan (disebut hantaran nol) sedemikian rupa, sehingga jika terjadi kegagalan isolasi, tercegahlah bertahannya tegangan sentuh yang terlalu tinggi karena pemutusan arus lebih oleh alat pengaman arus lebih.
4-8-2-1 Pentanahan sistem dan peralatan
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 190
Tegangan sentuh yang timbul pada beban peralatan atau instalasi akibat kegagalan isolasi sangat tergantung pada pentanahan. Bekerjanya alat-alat pengaman juga ditentukan oleh system pentanahan dan pentanahan sistem ini. Pentanahan system dalam distribusi tegangan rendah dilakukan pada titik bintang sumber (transformator distribusi atau generator) dan dalam jaringan distribusi serta badan/peralatan instalasi.
Secara garis besar ada 3 macam system pentanahan netral dan badan/peralatan instalasi, yaitu:
1) Sistem IT Titik netral terisolasi atau tidak diketanahkan (huruf pertama menyatakan isolasi), sedangkan badan peralatan diketanahkan. Dalam PUIL 1987, sistem IT ini dikenal dengan nama sistem penghantar pengaman atau HP. Titik netral trafo atau sumber tidak diketanahkan atau diketanahkan melalui tahanan yang tinggi (lebih dari 1000 Ohm). Sedangkan bagian konduktif terbuka peralatan, termasuk juga instalasi dan bangunan saling dihubungkan dan diketanahkan. Karena netralnya tidak diketanahkan, maka arus gangguan ke tanah yang jadi sangat kecil, yaitu hanya terdiri dari arus kapasitansi dan arus bocor instalasi serta arus detektor tegangan (bila digunakan). Persyaratan pentanahan ringan yaitu hanya maksimum 50 Ohm dengan tegangan satuannya hanya kecil. Karena arus gangguan kecil, pengaman arus lebih tidak akan bekerja karena kecilnya tegangan sentuh, sistem dimungkinkan operasi dalam keadaan gangguan satu fasa ke tanah atau badan peralatan. Pada waktu terjadi gangguan satu fasa ke tanah, tegangan antara fasa yang baik dengan tanah akan naik. Untuk mengetahui adanya kenaikan tegangan ini, dapat dipasang detektor (alat ukur tegangan) pada setiap fasa dengan tanah. Bila gangguan tidak dapat diperbaiki, akan terjadi kegagalan isolasi kedua di tempat lain pada fasa yang lain, maka akan terjadi gangguan hubung singkat yang besar dan alat pengaman akan bekerja. Sistem HP ini hanya dipakai dalam instalasi terbatas, misalnya dalam pabrik dengan pembangkit tersendiri atau trafo sendiri dengan kumparan terpisah, atau sumber listrik darurat portabel untuk melayani beban yang dapat dipindah-pindah.
2) Sistem TT Huruf pertama menyatakan pentanahan sistemnya ( titik netral trafo
atau generator), sedangkan huruf kedua menyatakan bagaimana hubungan peralatan atau instalasi dengan penghantar atau pengaman. Sistem TT berarti: (i) titik netral trafo (sistem) diketanahkan dan (ii) badan peralatan/instalasi dihubungkan ke tanah.
3) Sistem TN
Titik netral sistem di ketanahkan (huruf pertama T), badan peralatan atau instalasi dihubungkan dengan penghantar atau pengaman (huruf kedua N). Menurut PUIL, penghantar netral yang berfungsi juga sebagai
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 191
penghantar pengaman disebut penghantar NOL (IEC menyebutnya sebagai PEN conductor).
4-8-2-2 Sistem Pentanahan Netral Pengaman (PNP)
Bagian konduktor terbuka (BKT) peralatan atau perlengkapan dihubungkan dengan penghantar netral yang ditanahkan (penghantar nol) sedemikian rupa, sehingga bila terjadi kegagalan isolasi tercegahlah bertahannya tegangan sentuh yang terlalu tinggi karena bekerjanya pengaman arus lebih. Sistem PNP terdiri dari 3 jenis, yaitu:
1. Sistem PNP dengan penghantar netral yang sekaligus berfungsi sebagai pengaman untuk seluruh sistem (untuk penghantar tembaga yang lebih besar dari 10 mm2) (Gambar 4-170 C1)
2. Sistem PNP dengan penghantar netral dan penghantar pengaman sendiri-sendiri di seluruh sistem (untuk penghantar tembaga yang lebih kecil dari 10 mm2) (Gambar 4-170 C2)
3. Sistem PNP dengan penghantar netral yang sekaligus berfungsi sebagai pengaman untuk sebagian sistem , sedangkan bagian sistem yang lainnya, penghantar netral dan pengaman terpisah sendiri-sendiri. (Gambar 4-170 C1).
Persyaratan umum PNP
Gambar 4-170 Sistem Pentanahan TR
a) IT b) TT c) TN
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 192
Dalam PUIL 1987 pasal 313 B1, disebutkan bahwa luas penampang penghantar antara sumber atau trafo dan peralatan listrik, harus sedemikian rupa sehingga apabila terjadi hubung singkat antara fasa dengan penghantar nol atau badan peralatan, besar arus gangguan minimal sama dengan besar arus pemutus alat pengaman yang terdekat, yaitu IA = k. IN, di mana k adalah faktor yang nilainya tergantung pada karakteristik alat pengamannya.
Penghantar nol setidak-tidaknya harus diketanahkan pada titik sumber, di setiap percabangan saluran, ujung saluran dan di setiap pelanggan.Tahanan pentanahan total penghantar nol (RNE) harus tidak melebihi 5 Ohm, dengan alasan berikut bila terjadi gangguan ke tanah yang biasanya melalui tahanan gangguan RG, maka penghantar netral akan mengalami kenaikan tegangan sesuai persamaan berikut (tahanan penghantar diabaikan):
Pada umumnya harga tahanan gangguan yang kurang dari 17 Ohm
jarang terjadi. Batas tegangan sentuh yang aman menurut PUIL atau IEC adalah 50 volt.
4-8-2-3 Sistem PNP untuk JTR dan Instalasi Pelanggan
Pada jaringan tegangan rendah, penghantar netral berfungsi sebagai penghantar pengaman dan diketanahkan di sepanjang saluran. Titik
voltxRR
RVGNE
NENE 220
+=
Gambar 4-171 Sistem Pentanahan PNP
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 193
bintang trafo distribusi diketanahkan. Pada instalasi pelanggan, mulai dari PHB utama penghantar pengamannya terpisah tersendiri dari penghantar pengamannya, bila penampangnya kurang dari 10 mm2. Setiap pelanggan diharuskan memasang sebuah elektroda pentanahan melalui penghantar pentanahan yang tersambung ke rel atau terminal netral pengaman dalam PHB.
Tujuan pentanahan ganda pada penghantar netral sepanjang JTR dan pentanahan di setiap pelanggan adalah untuk:
a) Mencecah terjadinya tegangan yang terlalu tinggi pada penghantar netral, termasuk badan peralatan pelanggan bila terjadi gangguan satu fasa ke tanah ataupun hubungan singkat fasa netral, ataupun kegagalan isolasi peralatan.
b) Mencegah terjadinya kenaikan tegangan yang terlalu tinggi akibat terputusnya penghantar netral. Pada pelanggan yang netralnya terpisah dari sumber atau gardu distribusi.
c) Mencegah kenaikan tegangan kawat netral, termasuk badan peralatan, dalam hal ini ada arus netral akibat beban yang tidak seimbang.
d) Mencegah kenaikan tegangan yang terlalu tinggi pada kawat netralnya, bila JTR yang ada di bawah JTM menyentuh JTM.
Dengan tersambungnya penghantar pengaman ke netral maka bila terjadi kegagalan isolasi pada peralatan, arus gangguan akan lebih terjamin cukup besarnya sehingga alat pengaman selalu bekerja/putus dengan cepat, sebab penghantar netral merupakan jalan kembali yang baik, tidak hanya tergantung pada elektroda pentanahan pada sistem PP. Tegangan sentuh yang terjadipun relatif lebih rendah dibandingkan dengan sistem PP.
4-8-2-4 Bahaya Putusnya Penghantar Netral pada Sistem PNP Bila penghantar netral terputus, arus beban masih mungkin mengalir
melalui tanah, akibatnya akan terjadi kenaikan tegangan pada penghantar netral. Karena pengaman peralatan pelanggan terhubung ke netral, maka kenaikan tegangan netral tersebut akan dirasakan di badan peralatan pelanggan. Hal ini dapat membahayakan pelanggan. Bila pentanahan netral yang seharusnya dilakukan di titik-titik tertentu (di netral trafo distribusi, di tiang awal dan tiang akhir) tidak dilakukan, maka pada saat terjadi penghantar netral putus akan terjadi kenaikan tegangan pada fasa-fasa yang berbeban rendah dan penurunan tegangan pada fasa yang berbeban tinggi di jaringan yang penghantar netralnya tidak terhubung pada sumber.
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 194
4-8-3 Pengaman Terhadap Arus Lebih TR Pada umumnya gangguan pada jaringan distribusi disebabkan arus
lebih karena adanya hubungan singkat dan adanya perubahan atau perkembangan beban. Hubungan singkat yang dapat terjadi dalam distribusi tegangan rendah adalah :
- Hubungan singkat 3 fasa - Hubungan singkat fasa-fasa - Hubungan singkat satu fasa ke tanah
Dengan mengakibatkan reaktansi pada jaringan karena harga yang kecil dibandingkan tanahan jaringan, dan harga tanahan urutan nol, positif dan negatif sama besar, besar arus hubung singkat secara sederhana dapat ditentukan sebagai berikut :
Hubungan singkat 3 fasa Hubungan singkat fasa-fasa Hubungan singkat fasa ke tanah Hubungan singkat fasa netral
RUfIhs
1.13 =
RUffIhs 2
31.13 =
GEhs RRR
UgfI++
=1.1
Gambar 4-172 Kasus Putusnya Penghantar Netral pada Sistem PNP
Xhs RR
UNfI+
=1.1
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 195
U = Tegangan fasa netral (220 V) R = Tahanan Jaringan RG = Tahanan Gangguan RX = Tahanan pengantar netral RE = Tahanan pentanahan titik netral
Pada saluran tegangan rendah dengan penghantar telanjang
gangguan ketanah lebih sering terjadi dan dapat berupa : a) Kawat fasa putus dan menyentuh tanah b) Hubung singkat dengan penghantar netral c) Hubung singkat dengan crossarm/tiang
- Yang penghantar netral dihubungkan ke tiang - Yang menghantar netral tidak dihubungkan ke tiang
Jalan arus pada hubungan singkat ketanah
d) Sentuhan kawat fasa dengan pohon/benda e) Sentuhan SUTM dengan SUTR
Gangguan butir a dan b umumnya gangguan melalui tahanan yang cukup tinggi dan bahkan bisa mencapai ratusan ohm, tergantung kepada keadaan tanah ataupun ranting pohon, tanah atau ranting yang basah mempunyai tahanan yang lebih rendah dari pada tanah/ranting kering. Jadi
Gambar 4-173 Macam-macam hubungan singkat
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 196
arus gangguan dalam hal ini kecil dan adakalanya tidak cukup besar untuk mengoperasikan pelebur yang terpasang. Dalam hal hubungan singkat fasa netral, tahanan gangguan hampir mendekati nol sehingga arus gangguan akan besar sekali dan akan mengoperasikan pelebur.
Dalam hal hubungan singkat dengan crossarm yang penghantar netralnya dihubungkan ke tiang besi maka keadaannya hampir sama dengan hubungan singkat ke netral yaitu arusnya besar. Bila digunakan tiang harus ada penghantar pentanahan yang menghubungkan crossarm dengan elektroda pentanahan. Jika tiang besi tidak digunakan untuk mentanahkan kawat netral dan tidak tersambung ke netral, maka tahanan pentanahan akan tinggi (tiang besi ditanam 1/6 dari panjang tiang atau 1,5 – 2 m), bisa mencapai 50 ohm tergantung keadaan tanahnya arus gangguan relative kecil dan ada kalanya tidak cukup besar untuk menyebabkan beroperasinya pelebur di gardu. Bila tegangan sentuh yang timbul tidak berada dalam batas yang diizinkan, maka hal ini akan merupakan hal yang berbahaya bagi seseorang yang menyentuh tiang tersebut. Dalam hal sentuhan SUTM dengan SUTR diharuskan memakai sistim PNP dimana tahanan pentanahan secara menyeluruh rendah, maka gangguan ini akan memberikan arus yang besar tergantung pada pentanahan netral SUTM nya.
Pada penghantar berisolasi gangguan biasanya berawal dari gagalnya isolasi penghantar akibat panas yang berlebihan (beban lebih penghubung sadapan yang kurang kencang dsb) yang kemudian menular kepenghantar lain sehingga menimbulkan gangguan hubung singkat fasa-fasa netral dan bahkan hubungan singkat tiga fasa. Akibat yang ditimbulkan oleh arus singkat adalah :
1. Akibat thermis berupa hangus/lumernya isolasinya penghantar atau penghantar itu sendiri naiknya temperature minyak transformator.
2. Akibat pengasuh gaya elektro meknetis yang berupa bengkoknya penghantar/rel berayunnya menggelumbungnya tangki transformator.
4-8-4 Pengaman Arus Lebih TR Pengaman arus lebih di sisi tegangan ada beberapa macam :
1. No. Fus Breaker NFB No. Fuse Breaker adalah breaker/pemutus dengan sensor arus apabila arus yang melewati peralatan tersebut melebihi kapasitas maka sistim magnetik dan bimetalic pada peralatan tersebut akan bekerja dan memerintahkan breaker melepas beban.
2. Pengaman lebur (sekering) Pengaman lebur adalah suatu alat pemutus yang dengan meleburnya bagian dari komponennya yang telah dirancang dan disesuaikan ukurannya untuk itu membuka rangkaian dimana sekering tersebut dipasang dan memutuskan arus bila arus tersebut melebihi suatu nilai tertentu dalam jangka waktu yang cukup (SPLN 64 : 1985 : 1). Fungsi
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 197
sekering dalam suatu rangkaian listrik adalah untuk menjaga atau mengamankan rangkaian berikut peralatannya yang tersambung dari kerusakan dalam batas nilai pengenalnya setiap saat (PUIL 64:1985:24).
4-8-5 Menentukan Kapasitas Pengaman Lebur Untuk menentukan arus pengenal pelebur yang akan digunakan
patokan-patokan berikut :
a) Tegangan pengenal pelebur harus dipilih sesuai dengan tegangan jaringan yang akan diamankan.
b) Arus pengenal pelebur harus lebih besar dari arus beban penghantar. Untuk beban distribusi yang sebagian besar merupakan penerangan arus pengenal diambil sebesar 1,1 – 1,2 arus beban maksimum.
c) Arus beban maksimum sebaiknya diambil sebesar 0,8 x KHA penghantar.
d) Arus pengenal pelebur harus lebih kecil dari arus hubung singkat (yang terbaik adalah terhadap hubung singkat fasa – netral sedangkan hubung singkat fasa-fasa dan hubung singkat 3 fasa mutlak harus dapat diamankan) dititik terjatuh.
e) Untuk memberikan pengaman pada transformator distribusi harga ini tidak boleh melebihi angka di dalam tabel 5-11.
Contoh soal : Suatu gardu distribusi dengan kapasitas trafo 100 kVA 3
fasa mempunyai jaringan TR 2 jurusan dengan menggunakan kabel TIC A1 4 x 70 mm2. Panjang jaringan penjurusan 800 m.
Hitung : Besar arus pengenal lebur. Jawab : KHA TIC 70 mm2 dari tabel diperoleh 185 A (pada 400 C) Arus beban maksimum yang dianjurkan adalah 80 % x 185 A = 150 A Arus pengenal lebar 1,2 x 150 A = 180 A Kapasitas pelebur yang ada yang terdekat dengan 180 A adalah 160 A.
Gambar 4-174 Pengaman Lebur Tabung Tertutup
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 198
Dari tabel 5-10 untuk trafo 100 KVA 3 fasa, arus pelebur sekunder minimum 160 A. Dan maksimum 200 A jadi harga ini masih memenuhi. Sekarang akan dihitung kecepatan untuk memutuskan arus hubung singkat dititik ujung. Tahanan pengantar sampai dititik ujung = 0,8 x 0,54 Ohm = 0,432 Ohm. Arus gangguan fasa – netral.
Pada hubungan singkat fasa netral arus hubungan singkat akan diputus dalam waktu 40 detik (lihat gambar 4-175) Arus gangguan fasa-fasa ditik ujung adalah : Bila digunakan pelebur 160 A, dari gambar 3B arus 484 A ini akan dapat diputus dalam waktu 3,5 detik. Arus gangguan 3 fasa dititik ujung adalah : Dengan pelebur 160 A, arus ini akan diputus dalam 1,8 detik.
Tabel 4-11 Kuat Hantar Arus Pangeman Lebur Penampang
Nominal (mm2)
KHA (A)
Tahanan (Ohm/km)
Reaktansi 50 Hz (ohm/km)
1 2 3 4 3 x 25 + 50 105 1,52 0,10 3 x 35 + 50 135 1,10 0,10 3 x 50 + 50 145 0,81 0,10 3 x 70 + 50 185 0,54 0,10
Konstanta tahanan, reaksi dan KHA kabel pilin udara jenis NF A2X Pada suhu keliling maksimum 400 C.
Tabel 4-12. KHA Penghantar Tembaga A2C dan A3C
Penampang (mm2)
KHA (A) Tembaga A2C A3C
1 2 3 4
AmperexVI ff 484432,0432,022031.1
=+
=
AmperexI f 560432,0
2201.13 ==
RUI 1.1
1 =φ
AI 280432,043,0
2201.11 =
+=φ
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 199
25 160 145 135 35 200 180 170 50 250 225 210 70 310 270 255 95 380 340 320
120 440 390 365 150 510 455 425 185 585 520 490 240 700 625 585
Tabel 4-13. Rekomendasi pemilihan arus pengenal pelebur 24 kV jenis
letupan (Publikasi IEC 282-2 (1970). NEMA disisi primer berikut pelebur jenis pembatas arus (publikasi IEC 269-2 (1973)(230/400V) disisi sekunder yang merupakan pasangan yang diserahkan sebagai pengaman trafo distribusi.
Trafo Distribusi Pelebur Primer 24 kV Arus Pengenal (A)
Peleburan Sekunder (230/400 V)
Daya Pengenal
(kVA)
Arus Pengenal
(A)
Tipe T (A)
Arus Pengenal
(A)
Arus Pengenal
(A) Min Maks Min Mak
s Min Maks
16 1,3856 - - 6,3 6,3 80 100 25 2,1651 6,3 6,3 6,3 6,3 125 125 50 4,3301 10 10 10 16 250 250
Fasa Tunggal 20 kV 50 1,4434 - - 6,3 6,3 80 100
100 2,8867 6,3 8 6,3 10 160 200 160 4,6188 10 12,5 10 12,5 250 250 200 5,7735 10 12,5 16 20 315 315 250 7,2169 16 16 16 25 400 400 315 9,0933 20 25 20 31 500 500 400 11,5470 25 25 25 40 630 630*) 500 14,4330 25 31,5 31,5 40 800 800 630 18,1860 40 40 40 63 1000 1000 800 23,0940 50 63 50 80 1250*) 1250*)
Fasa Tunggal 20kV √3
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 200
1000 28,8670 63 63 63 100 1600*) 1600*) Catatan : Pemilihan nilai maksimum pelebur sekunder perlu
dikombinasikan dengan nilai maksimum pelebur primer. *) Diperoleh dengan pelebur primer
**) Contoh koordinasi terlihat
4-8-6 Koordinasi Pengaman Lebur Sistem pengaman lebur tidak bisa bekerja sendiri, perlu adanya koordinasi antara pelebur sisi primer dan sekunder pada trafo distribusi. Bila pada sisi primer trafo dipakai pelebur untuk pembatas arus, pelebur disisi primer bertugas menjaga batas ketahanan trafo terhadap gangguan hubung singkat
Gambar 4-175. Kurva leleh minimum dan kurva pemutusan maksimum dan pelebur tegangan rendah
Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 201
pada belitan trafo tetapi tidak sampai melebur karena inrush current. Sedangkan pelebur sisi sekunder bertugas mengamankan trafo dari arus lebih karena gangguan pada JTR untuk lebih jelasnya lihat tabel 5-10.
Gambar 4-176. Kurva leleh minimum dan kurva pemutusan maksimum dan pelebur tegangan rendah (230/400V) Berdasarkan rekomendasi IEC 269 – 2
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
202
TABEL BAB V JARINGAN DISTRIBUSI
TEGANGAN MENENGAH 5-1 Konsep Dasar dan Sistem 5-1-1 Ruang Lingkup
Sistem tegangan menengah s/d 35 kV, sistem konstruksi saluran udara, dan saluran kabel tanah. Dasar pertimbangan;
Ditinjau dari segi persyaratan teknis masih memenuhi syarat untuk digunakan dan dari segi ekonomis termasuk murah harganya dan jika ditinjau dari estetika (keindahan) maka kabel tanah hanya dipasang untuk keperluan keamanan dan keindahan pada daerah khusus karena biayanya masih relatif mahal. Dari segi pelayanan maka pemasangan kabel tanah akan menunjang kontinuitas pelayanan, karena tidak mudah terkena gangguan alam.
Gambar 5-1 Pola sistem tenaga Listrik
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
203
5-1-2 Karakteristik Perlengkapan Pada umumnya material-material utama perlengkapan distandarisir,
disesuaikan dengan karakteristik perlengkapan untuk mempermudah stock manajemen, mengurangi variasi penyediaan perlengkapan, Fasilitas gudang, dan menyederhanakan variasi tugas petugas, operasi.& pemelihara an.
Karakteritik teknis, contoh : PT: PLN (Persero) Distribusi DKI Jakarta & Tangerang, Material TM terdiri dari:
Rated insulation voltage , 24 kV V Test power frequency. 24 kV, 50 c/s Ketahanan Impulse (BTL.- SID) 125 kV Arus nominal .....A Test ketahanan hubung pendek 12,5 kA ,1 detik Short circuit making capacity 31.5 kA
5-1-3 Perlengkapan Hubung Bagi TR Gardu Distribusi Test power frekuensi tegangan fasa-fasa 2-3 Kv,1 menit Test ketahanan impulse 20 KV Test power frekuensi tegangan fasa-tanah 10 KV, 1 menit Arus nominal Busbar ....A Keseragaman acceptance test.
(Ageing test, impulse test, mechanical stength test, maintenance requirements, power frequency test, dan lainlain).
Short times with stand current dalam waktu 0,5 detik 5-1-4 Karakteristik Jaringan Distribusi Saluran Kabel Tanah
Pada gardu induk, pemutus tenaga dengan relai proteksi (non directional).
Jaringan penghantar; Multicore belted cable, Single belted cable, Ukuran 95 mm2, 150 mm2, 240 mm2, Tingkat kontinuitas pelayanan tinggi, Sistem 3 fasa dengan gardu distribusi kapasitas besar.
Struktur jaringan: Radial open ring, pada jarak yang sangat pendek dapat dipertimbangkan sistem radial.
Jangkauan pelayanan; maksimum 8 km panjang rute lintasan. Rugi tegangan; Diatur pada batas normal operasi dengan:
- Tap changer pada transformator tenaga di gardu induk (on-load). - Tap changer off load t 5 % pada gardu distribusi.
Gardu distribusi Gardu beton dengan dilengkapi:
- Load breakswitch pada kabel keluar - Isolating switch pada kabel masuk (Kadang-kadang dipakai juga load breakswitch pada kabel
masuk) Pengaman transformator dengan HRC fused.
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
204
Pembatas beban dengan relai pembatas dan trafo tegangan pada pelanggan tegangan menengah.
Gardu kiosk/metal (lad). - Perlengkapan sama dengan gardu beton. - Kapasitas 1 transformator maksimum 630 kVA.
Tingkat kontinuitas pelayanan. - Orde menit untuk pemulihan gangguan. - Orde detik (short break) pada gardu dengan memakai, network
protector (automatic change over). Pengaman Jaringan. - Relai overcurrent fasa-fasa dan groundfau4t relay pada gardu
induk. - HRC fused pada gardu distribusi untuk pengaman trafo. - Setting relai 0,47 detik pada gardu induk.
Pentanahan Sistem. - Memakai tahanan rendah 12 ohm pada transformator gardu
induk. - Membatasi arus gangguan tanah sampai dengan 1000 A selama 1
detik: Kontruksi Jaringan - Ditanam sedalam miimal 0,8 meter. - Untuk single core cable tiap 2 km, ditransposisi.
Transformator - Kapasitas transformator ukuran besar 250 kVA, 315 kVA, 400
kVA, 630 kVA, 1 MVA dengan 1 atau 2 trafo per gardu. 5-1-5 Karakteristik Jaringan Distribusi Saluran Udara
Pada gardu induk: pengaman circuit breaker dengan automatic redoser (pemutus balik).
Jaringan Penghantar - A 3 C, A 2C, ACSR - Single core cable - Twisted cable - Ukuran 35 mm2, 50 mm2, 70,mm2, 150 mm2, 187;5 mm2, 240
mm2. Secara umum penggunaan pada daerah dengan kepadatan beban rendah: - Pedesaan - Kota kecil - Daerah penyangga - Konstruksi " Antara"
Sifat Pelayanan - Jangkauan luas - Tingkat keandalan penyaluran relatif rendah
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
205
- Murah dan mudah dibangun. - Tingkat perawatan tinggi. - Pemeliharaan lebih sulit - Sistem 3 fasa dan atau 1 fasa.
Struktur Jaringan : - Umumnya beberapa tempat membentuk radial terbuka (open ring)
sesama fider utama. Pengaman Jaringan
- Circuit breaker pada gardu induk dengan relai overcurrent phasa-phasa dan groundfault non directional, dan directional untuk sistem PLN Distribusi Jawa Timur.
- Automatic redoser pada titik-titik tertentu. - Sectionalizer pada jaringan cabang - Cut-out fuse pada jaringan dengan cabangan ranting. - Pole switch pada tiap 4 km. - Arrester tipe 5.0 untuk tiang tengah dan tipe 10 KA untuk Tang
ujung serta pada gardu distribusi dan pertemuan dengan kabel tanah.
Gardu Distribusi • Beton
• Portal • Cantol (3 fasa, 2 fasa, 1 fasa)
Tiang penyangga. - Tinggi 11 m, 12 m, 13 m, 15m. - Kekuatan tiang : 200 daN, 350 daN, 500 daN, 800 daN, 1200
daN. - Jenis tiang
- Beton, besi - Kerangka
- Sela tanduk pada isolator gantung di tiang akhir dan isolator TM transformator.
Sistem Pentanahan - Pentanahan pada BKT Tang dengan nilai tahanan tanah
maksimum 10 ohm. - Pentanahan sistem bersama dengan penghantar netral
jaringan'Tegangan rendah. - Pentanahan sistem pada transformator gardu induk dengan
tahanan 40 ohm, 500 ohm dan atau solid grounded/ pentanahan langsung pada sistem jaringan netral bersama.
Kapasitas-kapasitas Transformator - Pada gardu beton, kapasitas besar. - Pada gardu portal/cantol, kapasitas 25 kVA, 50 kVA , 160 kVA, 250
kVA, 315 kVA, 400 kVA, sistem 3 fasa atau 25 kVA, 50 kVA satu fasa pada sistem jaringan netral bersama.
- Cut-out fused dan arrester untuk proteksi transformator distribusi.
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
206
- Gardu distribusi beton, portal, cantol.
5-1-6 Kontinyuitas Pelayanan Tingkat pelayanan yang akan diberikan menentukan aspek
teknis/ekonomis sistem yang diperlukan dan harga jual (tarif listrik) Tingkat pelayanan biasanya ditentukan oleh parameter:
- SAIDI (System Average Interuption Duration Index), adalah rata-rata indeks lama waktu padam
Contoh : Lama padam 2 jam selama 1 tahun - SAIFI (System Average Interruption Frekuency Index), adalah indeks jumlah kali padam dalam 1 kurun waktu. Misalnya : 12, kali gangguan selama 1 tahun.
Contoh pada PT. PLN (Persero), menentukan 5 tingkat pelayanan. - Padam orde beberapa jam. Contoh : SUTM tanpa sistem proteksi memadai (desadesa). - Padam orde maksimum 30 menit Misalnya pada daerah perkotaan. - Padam orde beberapa menit Misalnya sistem dengan sistem scada remote controlled (DCC-
UPD). - Padam orde beberapa detik. Misalnya dengan Automatic Switch. - Tanpa padam, spot load sistem yang dipasok dari 2
penyulang.
5-1-7 Langkah-langkah Meningkatkan Kontinyuitas Pelayanan Sistem proteksi jaringan (relai pentanahan, redoser). Sistem perlengkapan jaringan (pole switch, load break) Prosedur manuver (SOP) Sistem scada-unit pengatur distribusi (DCC-UPD). Manajemen pemeliharaan (SOP HAR, peralatan, dan lain-lain). Manajemen perencanaan sistem dan perencanaan
''penyambungan baru. Manajemen operasi (mobil unit, dinas gangguan). Manajemen komunikasi (radio area, unit operasi). Manajemen perbekalan (material harian) SDM yang kompeten dan profesional (KSA, iklat). PDKB Pemakaian saluran udara berisolasi, tree guard, pada daerah.
daerah rawan pohon. Pemakaian kawat tanah sebagai pelindung sambaran langsung
petir. Interloop antar penyulang.
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
207
5-1-8 Aspek Proteksi pada JTM Tujuan :
- Pengaman manusia/ lingkungan. - Pengamanan alat peralatan (kerusakan minimal) - Pelayanan, selektifitas pemadaman.
Macam-macam gangguan - Persistent/menetap - Umumnya pada SKTM - Non persistent/temporer, Umumnya pada SUTM
Jenis relay dan penempatannya - Pola proteksi pada saluran kabel tanah - Pada sisi 20 kV gardu induk transformator 150 kV/20 kV. - Overcurrent relay - OCR - OCR - Groundfault relay
PMT Penghantar tanah SSO Pembumian PBO CO HRC
REL- 20 kV ⟨⟨ ⟨⟨ ⟩⟩ ⟨⟨ ⟩⟩ OCR OCR-GF 150/20 kV OCR GF
BUSBAR 20 kV (REL)
- Overcurrent relay- Differensial relay - Pemutus balik otomatis
PBO : Pemutus Balik Otomatis (Automatic Redoser) SSO : Sakelar Seksi Otomatis (at. Sectionalizer) CO : Cut Out Fused HRC : HRC Fused pada Gardu Beton
Gambar 5-2 Pola proteksi pada saluran udara tegangan menengah
Gambar 5-3 Pola proteksi pada saluran kabel tanah
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
208
5-1-9 Aspek Proteksi pada Pembangkit - Tegangan keluar pembangkit diatas 1 MW umumnya dengan
pengenal 1 s/d 11 kV. - Jadi persyaratan A.L. PHB utama juga dilengkapi dengan relai-relai
elektris.
- Relai daya balik - Relai OCR - Relai diferensial - Relai GF - Relai sinkronisasi - Relai arus sisa - Relai UFR (Under Frequency Relay) - Relai over speed - Relai thermis
5-1-10 Aspek Pembumian pada JTM Pembumian JTM dilakukan pada titik bintang transformator tenaga. φ L1 φ L2 φ L3 Z 5-1-11 Aspek-aspek Pembumian titik netral transformator tenaga
di Garduk Induk pada - Kerusakan akibat hubung pendek jaringan. - Keselamatan lingkungan. - (manusia, mahluk hidup) akibat hubung pendek dengan JTR.I - Selektifitas penyulang yang mengalami gangguan. - Pengaruh terhadap sistem telekomunikasi. • Faktor 1,2,4 menghendaki arus gangguan rendah. • Faktor 3 menghendaki arus gangguan besar.
5-1-12 Pola jaringan TM berdasarkan aspek pembumian Pola jaringan melalui pembumian tahanan rendah. a). R = 12 ohm, sistem 3 fasa, 3 kawat untuk saluran udara.
Gambar 5-4 Pola proteksi pada pembangkit
[Z] rendah : 40, 20 Ohm [Z] tinggi : 500 Ohm [Z] kecil : < < < < [Z] besar : Mengambang
Gambar 5-5 Aspek Pembumian pada JTM
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
209
R = 40 ohm, sistem 3 fasa, 3 kawat untuk saluran kabel tanah. Contoh : Jakarta, Jabar, Luar Jawa. b). Pola Jaringan melalui pembumian tahanan tinggi R = 500 ohm. Contoh di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur.
c). Pola jaringan melalui pembumian langsung. R = 0 / kecil sekali Contoh : sistem 3 fasa, 4 kawat multi grounded system di Jawa
Tengah. d). Pola jaringan tanpa pembumian tidak ada pembumian netral
pada sisi TM. Umumnya di luar Jawa
5-1-13 Karakteristik jaringan dengan pembumian tahanan rendah
Contoh di PT. PLN (Persero) Jakarta Raya Sistem jaringan 3 fasa 3 kawat. Jaringan radial atau radial open - loop. Sistem proteksi dengan: Overcurrent relay untuk gangguan phasa-phasa.
Groundfault relay, gangguan hubung tanah. HRC fused dan cut-out fused untuk pengaman
transforrnator Arrester untuk pengaman petir •
Relay murah Pengaruh tegangan langkah kecil Pemakaian peralatan proteksi lebih mudah. Pengaruh gangguan magnetik pada saluran telepon relatif
kecil. Sistem 20 KV : . [z] = 20 ohm → I Gangguan : 1000 A [z] = 40 ohm → I Gangguan : 300 A
5-1-14 Karakteristik jaringan dengan pembumian tahanan tinggi Contoh di PT. PLN (Persero) Jawa Timur Sistem 3 fasa, 3 kawat. Jaringan radial atau radial open - loop. Sistem proteksi :.
Overcurrent differential relay dengan automatic recloser pada circuit breaker gardu induk.
Automatic recloser pads seksi-seksi jaringan dengan sensor tegangan
Automatic sectionalizer pada pencabangan jaringan Cut - out fused untuk pengaman transformator Arrester
untuk pengaman petir Relay mahal → memakai relai arah (directional relay)
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
210
Selektifitas dan koordinasi dengan pengaman lain memakai sensor tegangan.
Gangguan terhadap saluran telekomunikasi kecil. [Z] = 500 ohm. I gangguan ≈ 24 A
5-1-15 Karakteristik jaringan dengan pembumian langsung
Contoh di PT. PLN (Persero) lawa Tengah Sistem jaringan 3 fasa, 4 kawat (Multi grounded system).
SUTM dengan kawat netral sisi TM dijadikan satu dengan kawat netral sisi TR, yang ditanahkan setiap 500 meter.
Jaringan umumnya radial. Gardu distribusi type portal dengan transformator 3 fasa dan type cantol dengan transformator 1 fasa.
Sistem proteksi - Overcurrent relay dengan automatic recloser, berkoordinasi
dengan sectionalizer pada seksi-seksi tertentu saluran utama clan pencabangan.
- Cut - out fused 1 fasa pada saluran pencabangan 1 fasa. - Cut - out fused untuk pengaman trafo. - Arrester untuk pengaman petir. - Relai murah, arus gangguan besar - Cocok untuk jangkauan jaringan luas. - Koordinasi dengan pengaman sisi hilir mudah - Perlu kawat tanah pada sisi TM.
5-1-16 Karakteristik jaringan tanpa pentanahan
Umumnya listrik desa dengan trafo distribusi sebagai step up dari sisi TR kesisi TM.
Hanya ada pengaman cut-out clan arrester pada transformator distribusi. Kadang-kadang dilengkapi relai tegangan tidak seimbang pada penyulang TM keluar.
Apabila terjadi gangguan tanah UFR mesin PLTD jatuh.
5-1-17 Titik pembumian pada sistem TM
Pada titik netral transformator tenaga. Pada jaringan saluran udara TM tiap 3 tiang. Pada arrester. Pada terminasi kabel masuk sel gardu induk Pada titik netral transformator distribusi. Semua BKT dibumikan.
Nilai R : Maksimum 10 ohm pada tiang Maksimum 0,2 ohm pada titik netral transformator distribusi.
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
211
5-1-18 Titik-titik pembumian pada jaringan TM
TRAFO TENAGA (1) Z
(6) REL 20 KV GI ∧ ∧ ∨ ∨ TM MOF KABEL
PENGHANTAR NETRAL (4) BKT TRAFO DISTRI BUSI R
TIANG (2) ARRESTER (6) (2) (3) TR
5-1-19 Ketentuan-ketentuan Tentang Persyaratan Instalasi Tegangan Menengah PUIL 2000
PUIL 2000 mencakup persyaratan-persyaratan instalasi listrik sampai dengan tegangan 35 kilo Volt dalam bangunan dan di luar bangunan, mencakup:
Perancangan, Pemasangan, Pemeriksaan, Pengujian, Pelayanan, Pemeliharaan, Pengawasan.
Bahasan-bahasan pada persyaratan instalasi jaringan distribusi tegangan menengah berikut ini adalah bahasan-bahasan mengenai persyaratan instalasi baik pada jaringan ataupun gardu listrik.
Standard-standard konstruksi yang ada dan dipakai khususnya terbitan PT. PLN (Persero) digunakan sebagai contoh aplikasi.
Gambar 5-6 Titik-titik pembumian pada jaringan TM
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
212
5-1-20 Susut Tegangan pada Sistem 3 fasa 3 kawat 20 kV Susut tegangan pada jaringan distribusi TM dibatasi dengan batas-batas sadapan pada transformator distribusi. Contoh : Sadapan transformator distribusi ± 5 % pada tegangan
pelayanan/tegangan nominal.
Namun apabila akan dihitung besarnya susut tegangan pada jaringan jika memikul beban dapat dilakukan dengan berbagai metode.
Metode perhitungan dapat dilakukan antara lain dengan: - Metode impedansi jaringan Perhitungan secara klasik impedansi jaringan dan arus
beban. - Metode momen listrik. Perhitungan berdasarkan tabel-tabel momen listrik yang
telah disusun. - Metode grafis
Perhitungan berdasarkan kurva-kurva susut tegangan, panjang jaringan, penampang hantaran dan jenis hantaran.
- Perhitungan berdasarkan tabulasi susut tegangan per km jaringan.
Uraian-uraian berikut diambil contoh untuk metode moment listrik, mengingat metode ini paling mudah diterapkan.
Tabel 5-1 adalah nilai momen listrik untuk cos φ = 0,8
Tabel 5-1. Momen listrik kabel dan hantaran udara TM (20kV) pada beban diujung penghantar dengan susut tegangan 5%
SISTEM JENIS PENGHANTAR
LUAS PENAMPANG (MM2)
DAYA MAX(MVA)
MOMEN LISTRIK
(MVA.KM) kHA (A)
KABEL TANAH
TEMBAGA 50 5,8 46,7 168 TEMBAGA 95 8,7 83,3 250 TEMBAGA 150 11,4 116,1 328
ALUMINIUM 95 7 54,4 200 ALUMINIUM 150 9,2 78,9 266 ALUMINIUM 240 12,6 117,2 365
PENGHAN-TAR UDARA
TEMBAGA 25 5 2,5 145 TEMBAGA 35 6,1 33 177 TEMBAGA 50 8 40,6 230 TEMBAGA 70 9,4 50 270
ACSR 187,5 13,9 60,9 400 ACSR 270 17,7 72,9 510
ALUMINIUM 110 48 310 ALMELEC 35 5 19,4 145 ALMELEC 70 7,8 33,3 225 ALMELEC 150 12,6 55,5 365 ALMELEC 228 16,6 69,4 480
Catatan : kHA pada t = 35OC
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
213
5-1-21 Metode momen listrik Sistem 3 fasa 3 kawat 20 kV Parameter suatu momen listrik adalah besarnya faktor daya (= cos φ) jaringan, berdasarkan persamaan klasik:
∆V = √3. I ( R cos φ + jwL sin φ) Overheating cable t = 35OC, 1 kabel pada 1 jalur konstruksi
Contoh:
a. Suatu beban diujung 10 MVA dengan rugi tegangan 5 % .
L = 60,9 = 6,09 km 10
b. Kabel tanah tembaga 3 x 95 mm2 beban 4 MVA pada L = 10 km.
∆µ = 4 x 10 X 5% = 2,4 =2,4% 83,3 100
c. Berapa besar beban jika saluran tembaga L = 25 km, ∆µ = 7%
P = 33 X 7 = 1,848 MVA. 25 5
5-2 Saluran Kabel Tanah Tegangan Menengah Kabel tanah Tegangan Menengah yang dipakai adalah kabel tanah
dengan pelindung mekanis bagian luar (pita baja), dengan berpelindung medan magnet dan elektris. Kabel dapat berbentuk multicore belted cable atau single core full isolated cable. Dipakai kabel Alluminium berurat dipilin dengan bahan isolasi XLPE. Pada umumnya kabel tegangan menengah ini terdiri atas 3 x 1 core atau 1 x 1 core dengan ukuran penampang 300 mm2, 240 mm2, 185 mm2, 150 mm2, 70 mm2, dan 25 mm2. Pemilihan pemakaian tergantung beban/kerapatan beban yang dilayani.
Kabel tanah diletakkan pada minimum: - 0,8 meter di bawah permukaan tanah pada jalan yang dilewati
kendaraan. - 0,6 meter di bawah permukaan tanah pada jalan yang tidak dilewati
kendaraan. - Lebar galian sekurang-kurangnya 0,4 meter
Catatan: Ketentuan ini sangat bergantung pada peraturan daerah setempat. Contoh di Jakarta kabel digelar pada minimum 1,1 meter di bawah permukaan tanah.
Kabel harus dilapisi pasir halus setebal minimum 5 cm dari permukaan kulit kabel dan bagian atas diberi pelindung mekanis untuk maksud keamanan terbuat dari beton, batu atau bata (lihat gambar penampang galian kabel tanah menurut standard konstruksi PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Tangerang). Kabel tegangan lebih tinggi berada di bawah yang bertegangan rendah.
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
214
5-2-1 Konstruksi persilangan kabel telekomunikasi dan kabel listrik non PLN.
- Kabel listrik harus di bawah kabel telekomunikasi kabel harus dilindungi dengan pelindung (pipa beton belah, plat beton, pipa yang tahan api). Kedua sisi persilangan pelindung di tambah 0,5 meter.
- Jika jarak antara kabel tanah dengan kabel telekomunikasi kurang dari 0,5 meter pelindung harus di dua kalikan (tambahan pelat beton).
- Bila kabel telekom sejajar dengan kabel TM panjang selama sejajar harus dimasukkan dalam pipa beton belah, pelat beton atau sejenis.
- Jarak kabel tanah dengan instalasi telekom minimal 0,3 meter dan harus diberi pelindung (termasuk tiang telekom). (lihat standard konstruksi PT. PLN (Persero) ).
5-2-2 Persilangan kabel tanah TM dengan rel kereta api, - Rel ka bel harus berjarak minimal 2 meter dari rel kereta api. - Jika terjadi persilangan, kabel harus dimasukkan dalam pipa gas
dengan diameter minimal 4 inchier (10 cm) dan diiebihkan 0,5 meter dari masing-masing garis vertikal kid kanan rel kereta dengan kedalaman 2 meter dibawah rel kereta api.
- Hal yang sama jika melintas dipekarangan atau bangunan PT. KAI.
Catatan: 1. Harus dilaksanakan pengaturan agar kabel dapat diambil kembali
dengan tidak usah menggali lagi bagian bawah jalan kereta api 2. Pekerjaan yang dilaksanakan di atas tanah milik PJKA agar
dilakukan oleh kontraktor yang disetujui PJKA 3. Sama halnya dengan perlintasan pada jalan raya, pada
penyebrangan jalan kereta api juga harus ditambahkan 2 pipa cadangan.
Gambar 5-7 Aturan Penanaman Kabel
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
215
5-2-3 Persilangan dengan jalan raya atau jalan lingkungan. - Kabel harus di masukkan kedalam pipa beton atau PVC atau selubung
baja, yang diiebihkan masing-masing 0,5 meter sisi kiri
- Dibawah penerangan, melintasi jalan lingkungan kabel harus dilindungi dengan pelindung pipa beton separuh, PVC atau sejenis.
5-2-4 Persilangan dengan saluran air dan bangunan air. - Kabel harus ditanam minimal 1 meter di bawah saluran air. Jika
dibawah laut harus ditanam sedapat mungkin 2 meter di bawah dasar laut.
- Jarak minimal kabel tanah dengan bangunan air adalah 0,3 meter dan harus dimasukkan kedalam pipa beton/logam dengan diameter minimal 10 cm dan dilebihkan 0,5 meter pada kedua sisi perlintasan.
- Pada kedua tepi saluran air dimana kabel tanah ditanam harus diberi tanda yang cukup untuk dilihat pengemudi kapal.
- Jika harus menyeberangi saluran air jembatan kabel khusus harus tersedia.
5-2-5 Pendekatan kabel dengan konstruksi instalasi diatas tanah. - Jarak kabel minimal 0,3 meter dari kaki keluar konstruksi dan harus
dilindungi dengan pipe baja atau bahan yang kuat, tahan lama, tahan api. Jika jaraknya kurang dari 0,8 meter dan diberi tambahan 0,5 meter dari sisi kin kanan lintasan.
- Kabel keluar dari tanah (opstik kabel) pada tiang harus dilindungi pipa galvanis minimal panjang 2,5 meter di atas tanah.
5-2-6 Prosedur Peletakan Kabel Tanah - Kabel diletakkan minimal berjarak 2 x diameter kabel atau 20 cm dari
kulit luar kabel.
- Perletakan kabel yang lebih dari 2 kabel baik vertikal atau horizontal mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kondisi ini menurut KHA kabel faktor perkalian ini disebut faktor perletakan, untuk jelasnya lihat 7.3-34 s/d 7.3-35 PUIL 2000. (berlaku untuk perletakan di udara atau di tanam).
- Pada tiap jarak 5 meter jalur kabel harus diberi patok tanda kabel. - Pada tiap sambungan kabel harus diberi patok tanda sambungan
kabel.
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
216
Gambar 5-8. Pekerjaaan sebelum penanaman kabel
Jumlah kabel
L cm
2 3 4 5 6
60 90
120 150 180
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
217
Contoh:
5-2-7 Ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat dalam PUIL
- Lintasan di atas rel kereta api. D ≥ 1,5 meter di atas fasilitas kereta api (misalnya tiang rel-kereta listrik) - Jarak tiang terhadap rel kereta api. D ≥ panjang tiang. - Lintasan dengan SUTT. D ≥ 3 meter ( 70 kV) D ≥ 4 meter (150 kV) - Jarak terhadap tower transmisi D ≥ tinggi tiang atau D ≥ 1,5 tinggi tiang - Lintasan di atas jalan raya utama D ≥ 6 meter pada temperatur 60O C tanpa angin - Sudut lintasan maksimum dengan jalan raya utama atau sungai sebesar
30O C - Lintasan di atas saluran/sungai, minimum 6 meter saat air pasang
ditambah 1,5 meter diatas tiang layar. (untuk sungai besar tidak dianjurkan saluran TM melintasi sungai).
5-2-8 Persiapan Pelaksanaan Penggelaran Kabel Tanah - Persiapan gambar rencana pelaksanaan pada peta 1 : 5000 atau 1:
200 - Survai dalam pembersihan jalur kabel. - Penggalian titik kontrol jalur kabel pada tiap 50 meter (injeksi test
galian) untuk meneliti kemungkinan adanya utilitas lain. - Check dokumentasi asbuilt drawing utilitas-utilitas lain. - Persiapan material penunjang (Pasir urug, Batu patok/tanda, Batu
peringatan, Pipa beton/PVC/ sejenis). - Pekerjaan pendahuluan telah dilaksanakan Lintasan/Crossing-
Boring,
Gambar 5-9. Peletakan Kabel Tanah
> 2cm 2 D 2 D (20 cm) (20 cm)
In = Arus minimal kabel = 260 A.
Fp = Faktor perletakan untuk 3 kabel mendatar = 0,88
In' = Arus nominal yang dikoreksi 0,88 x 260 A = 240 A.
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
218
- Jembatan kabel, Pembersihan rencana jalur kabel, Rambu-rambu K3, Alat-alat kerja (rol kabel, dan lain-lain).
- Pelaksanaan penggelaran/penarikan kabel dengan 1 supervisor, 1 mandor, 1 kuli tiap 5 meter. Berikut ini adalah gambar perlengkapan persiapan penanaman kabel
tanah dan alat angkut untuk menunjang pemasangan kabel tanah dan selanjutnya gambar-gambar pekerjaan sebelum penanaman kabel tanah.
Gambar 5-10 Pengangkutan kabel tanahtegangan menengah dengan forklif
HASPEL
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
219
R > 15d
Gambar 5-12 Saluran Kabel Tanah
Gambar 5-11 Alat pelindung dari seng
HITAM
120
Gambar 5-13. Penentuan lintasan Kabel Tanah
5-2-9 Menentukan jalan lintasan kabel
- Kabel-kabel listrik lebih baik ditempatkan pada tanah umum (negara) dibawah trotoir (jalan setapak).
- Membelokkan arah kabel dilaksanakan dengan cara membuat lengkungan sekurang- kurangnya dengan radius lekuan (bending radius) 15 kali diameter keseluruhan daripada kabel yang bersangkutan.
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
220
Gambar 5-14. Lebar Galian dan Penanganan Kotak Sambungan
Gambar 5-15 Dasar lubang galian
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
221
MENYEBERANGI PIPA ATAU KABEL
JALAN MASUK KE RUMAH
Gambar 5-16 Aturan Penamanan Kabel
Gambar 6-17. Jembatan Kabel
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
222
Gambar 5-18 Konstruksi khusus penanaman kabel
Gambar 5-19 Lintasan penyebrangan kabel tanah pada gorong-gorong/parit
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
224
Gambar 5-21 Buis Beton
Gambar 5-22 Konstruksi Penanaman Kabel Tanah
- PVC AW 6 mm di cor di dalam beton 1 : 3 : 5
- Untuk kontrol dibuat bak kontrol tiap-tiap 50 m satu buah bak kontrol dengan luas 2x3 m dan dalamnya 1,40 m
Konstruksi Beton Konstruksi itu terutama untuk ketahanan kabel, letak dan posisi serta ada rencana pengembangan, seperti di lokasi sekitar GI
DETAIL SAMBUNGAN (dalam cm)
BUIS BETON
1000
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
226
Gambar 5-24 Posisi/kedudukan kabel di dasar rak kabel
Potongan A - A
POTONGAN MEMANJANG
POSISI/KEDUDUKAN KABEL
Rak penyangga kabel
Ruang bebas 1 m
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
227
Penanganan dan Pengangkutan Haspel - Haspel harus digerakkan
dengan tangan secara hati-hati. - Haspel harus di gusur atau
digelindingkan - Haspel tidak boleh diikat dengan
rantai, kabel atau tambang seputarnya karena akan menekan bagian luar kabel.
- Haspel sama sekali tidak boleh dilemparkan ke tanah dari atas truk atau trailer.
Gambar 5-25 Penanganan dan Pengangkutan dengan Haspel
- GRIP PENARIK BERMATA SATU
Gambar 5-26 Alat Penarik Kabel
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
228
Roller untuk Kabel
Gambar 5-27 Alat Penarik kabel (Grip)
Gambar 5-28 Roller untuk Kabel
- GRIP PENARIK BERMATA DUA
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
229
Gambar 5-29 Roll Penggelar Kabel
Gambar 5-31 Penarikan kabel TM dengan Roll
dibelokan normal Belokan Normal
Gambar 5-30 Dongkrak Kabel
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
230
Gambar 5-32 Penarikan kabel TM Belokan Tajam
R > 20d d = diameter
Gambar 5-33 Penggelaran Kabel
Melepas Gulungan Kabel - Apabila perlu, boleh tidak seperti biasanya, kabel di lepas dari haspel
nya, diletakkan di atas tanah di luar bagian (cara melepas gulungan). - Pekerjaan yang rumit ini harus dilaksanakan hanya oleh para pekerja
yang ahli di bawah pengawasan mandor/pengawas. - Harus di tempuh segala upaya untuk mencegah jangan sampai kabel
melintir ketika di tarik ke dalam (galian).
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
231
5-3 Penyambungan kabel tanah 5-3-1 Ujung kabel sebelum penyambungan - Apabila dua kabel akan di sambung, maka kedua ujung yang akan
disambung itu harus dilebihkan satu dari yang lainnya sepanjang 1 meter.
- Sebagai ketentuan umum, kabel pada setiap sisi kotak sambungan tidak dilebihkan panjangnya.
5-3-2 Tutup/Dop Ujung Kabel - Kabel di dalam lubang galian, baik sesudah maupun sebelum diurug, harus
dipasangkan tutup/dop ujungnya sebagaimana mestinya atau diperiksa apakah betul sudah baik pemasangannya.
- Dalam hubungan ini perlu diperhatikan, agar di antara ujung kabel dengan tutup/dop ujung kabel harus ada bagian kabel yang dikupas bersih.
Gambar 5-34 Persiapan Penyambungan Kabel
Gambar 5-35 Tutup / Dop Ujung Kabel
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
232
- Ruang bebas yang harus disediakan untuk kotak sambung (Juntion box)
5-3-3 Memberi label nama pada kabel bawah tanah - Agar pemberian tanda kabel bawah tanah lebih mudah, maka akan
diberi label-label tanah dengan jarak antara yang sama (setiap 6 meter). Label-label ini akan dicetak seperti contoh ini.
- Permukaan label timah yang ada tulisannya itu akan diletakkan diatas kabel : label itu akan diikat dengan kawat yang digalvanizir.
Gambar 5-36 Aturan galian penyambungan
Gambar 5-37 Penamaan Timah Label
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
233
5-3-4 Pemberian tanda pada kotak sambungan (junction box)
Catatan: Label-label harus ditempatkan sedekat mungkin dengan kotak sambung
Mengubah mengatur kembali jaringan tenaga listrik yang sudah terpasang/beroperasi: Sebelum membuat sesuatu perubahan terhadap sistem jaringan yang sudah terpasang harus diambil langkah-langkah sebagai berikut:
- putuskan saluran listrik pada kabel dan hubungkan kedua ujung kabel ke dalam tanah;
- bila galian sudah terbuka, lepaslah kedua kabel dan periksalah apakah nama, jumlah, seksi, tegangan, tahun penanaman sesuai dengan apa tertera pada gambar;
- pastikan bahwa kabel yang akan dipotong telah benar dengan menggunakan alat deteksi kabel (radio detection)
- pengawas pekerjaan dari PLN harus memeriksa apakah pada bagian kabel yang akan dipotong itu sudah tidak bertegangan.
5-3-5 Peralatan untuk memeriksa tegangan listrik
Gambar 5-38 Pemasangan Lebel pada Kotak Sambung
Gambar 5-39 Alat Pembumian Kabel yang akan dipotong
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
234
Tutup asbes (Asbestos cover) Tebal : 4 mm Ukuran : 90 x 90 Cm Prosentase asbes sekurang- kurangnya 90%
5-4 Saluran Udara Tegangan Menengah 5-4-1 Prosedur Penggelaran Kabel Tegangan Menengah.
a. Kabel inti tunggal tegangan menengah harus dilakukan transposisi pada tiap jarak 4 meter
b. Transportasi kabel dilakukan secara gelondongan/haspel. Penggelaran harus memakai besi penyangga agar haspel mudah diputar.
Karpet Isolasi
Sarung tangan berisolasi
Catatan: 1. Sarung tangan harus dibawa dalam tas khusus 2. Periksa keadaan sarung tangan sebelum dipakai
Gambar 5-40 Tutup Asbes
Gambar 5-42 Alat Kerja Pembumian
0,50
m
1,00 m
Tegangan uji 30 atau 20 kV
Penampang : 60 mm2
Panjang : 2 meter
Gambar 5-41 Anyaman penghubung
Anyaman penghubung ( connecting brand)
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
235
c. Jika kabel sangat pendek di bawah 30 meter transportasi dapat dilakukan tanpa haspel namun kabel diangkut dalam gelondongan menyerupai angka 8.
d. Untuk mencegah deformasi penampang kabel, tidak diperboleh- kan tergilas kendaraan umum.
e. Peralatan kerja yang diperlukan; Dongkrak/penyangga kabel, rol datar dipasang tiap jarak 5 meter, rol belok, rol tikungan, penarik ujung kabel, peralatan penggulung.
f. Sebelum digelar, dilakukan penyuntikan guna mendapatkan kemungkinan adanya fasilitas-fasilitas lain di dalam tanah.
g. Penggelaran dilakukan per haspel. h. Setelah penggelaran lubang galian harus di timbun kembali. i. Kabel di beri identitas yang terbuat dari logam timah/dyno dengan
mencantumkan; nama pelaksana/jointer, tanggal penyambungan, nama kabel, merk sambungan, kode sambungan.
5-4-2 Mengidentifikasi masalah penggelaran SKTM a. Hal-hal yang harus diperhatikan di dalam penggelaran kabel tanah
adalah pengawasan pada saat menggelar kabel, baik kabel itu sudah dalam kemasan haspel atau dalam bentuk gulungan membentuk angka 8. Hal ini menyangkut keamanan dan keselamatan pada saat pembebanan kabel.
b. Jika terdapat kabel ciri/cacat pada selubung atau isolasinya (terutama isolasi) yang disebabkan oleh kesalahan pada saat penggelaran, akan mempengaruhi KHA kabel. Walaupun pada setiap kabel sudah mempunyai batas toleransi (faktor koreksi), terutama pada kabel yang dibebani terus-menerus.
5-4-3 Membuat laporan a. Setiap akhir pekerjaan wajib membuat peta pelaksanaan (asbuilt
drawing) pada peta 1: 200 dan peta 1:5000 yang mencamtumkan; nama penyulang/kabel, titik sambungan, posisi perletakan kabel, tanggal dan nama pelaksana, jenis kabel, posisi transposisi jika memakai single corecable/kabel inti tunggal, posisi lintasan kabel dengan inti lintasan lain, nomor haspel.
b. Dokumentasi pelaksanaan (photo/gambar pelaksanaan)
c. Laporan pelaksanaan, nomor perintah kerja.
5-4-4 Kotak Sambung dan Kotak Ujung Saluran Kabel Tegangan Menengah
5-4-4-1 Merencanakan dan mempersiapkan pemasangan kotak sambung dan kotak ujung SKTM
a. Sambungan kabel tanah setelah penggelaran tiap 1 haspel (± 300 meter) perlu disambung.
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
236
b. Tata cara penyambungan sesuai dengan teknologi yang dianut dan dilakukan oleh pelaksana bersertifikat. Contoh: metode Raychem, Premoulded, 3m dan lain-lain.
c. Hal yang sama dengan terminasi kabel. d. Sambungan terminasi kabel pada saluran udara penghantar tak
berionisasi harus dilindungi dengan Arrester. Arus pengenal Arrester 5 kA, jika sambungan di tengah saluran. Arus pengenal Arrester 10 kA, jika sambungan di ujung saluran.
e. Pada titik sambungan kabel harus diberi cadangan lintasan dengan cara digelar seperti gambar berikut → Demikian pula pada kabel yang naik tiang kesaluran udara.
5-4-4-2 Memasang kotak sambung Ada 2 macam sambungan berdasarkan tempatnya: a. Sambungan yang mengalami tegangan tarik dipakai tention joint /
joint sleve b. Sambungan yang tidak mengalami tegangan tarik dipakai non tention
joint / Connector atau paralel groove yaitu pada section pole. Paralel groove ini dipakai agar bisa dibuka waktu mencari gangguan, pemakaiannya harus double per phasa karena konduktiviti parallel groove ini hanya 60% dari konduktiviti kawatnya per buah. Section pole / tention pole sendiri dipasang pada setiap ± 10 gawang dan pada tention pole ini paralel groove dipasang.
5-4-4-3 Mengidentifikasi masalah pemasangan kotak sambung dan kotak ujung
a. Hal-hal yang harus diperhatikan di dalam pemasangan kotak sambung adalah pengawasan pada saat menyambung kabel, jangan sampai terdapat celah atau cacat lubang (void) yang bisa menyebabkan timbulnya udara atau air yang menerobos ke dalam kotak sambungan, sehingga bisa terjadi arus bocor atau flesh over.
b. Permukaan kontak antara kedua kabel yang disambung harus seluas mungkin sehingga tidak akan mempengaruhi/mengurangi KHA kabel. Walaupun pada setiap sambungan kabel sudah mempunyai batas toleransi (faktor koreksi), terutama pada kabel yang dibebani terus-menerus. Namun demikian secara praktis sulit dicapai pada sambungan agar KHA tidak berkurang.
5-5 Konstruksi Saluran Udara Tegangan Menengah 5-5-1 Ketentuan-ketentuan Melaksanakan Konstruksi Saluran
Udara Tegangan Menengah (sesuai PUIL 2000) Penghantar udara telanjang yang di pasang, direntangkan diatas tiang
penyangga dengan isolator penunjang.
Persilangan saluran udara dengan saluran telekomunikasi dengan jarak
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
237
Gambar 5-43 Jarak aman antara kereta api dengan tiang
- Penghantar telanjang berjarak 1 meter, bersilangan 1 meter. - Penghantar berisolasi berjajar 1 meter, bersilangan 1 meter.
Pemasangan saluran udara TM dengan saluran telekomunikasi harus lebih besar dari jarak 2,5 meter.
Pemasangan pada satu tiang saluran udara TM dengan saluran udara TR (underbuilt) pada setiap 3 tiang harus di pasang penghantar pembumian yang dihubungkan dengan penghantar netral.
Contoh : Lihat standard konstruksi PT. PLN (Persero).
Jarak aman saluran udara terhadap bagian yang terhubung dengan bumi adalah minimum 5 cm + 2/3 x kV sistem. . Contoh : 5 cm + 2/3 x 24 kV = 5 cm + 16 cm = 21 cm, (Pada tabel 4.131 PUIL tercantum 60 cm untuk Tegangan kerja 20 kV). Namun jarak aman saluran pada lingkungan umum ditentukan juga oleh pemerintah daerah.
Jarak antara 2 penghantar saluran udara TM (%20 kV) minimal 60 cm.
Jarak minimum lendutan penghantar terhadap tanah adalah 6 meter. (menurut PUIL-2000, cukup 5 meter).
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
238
Gambar 5-44 Jarak aman antara SUTT dan SUTM
Gambar 5-45 Jarak aman antara Menara SUTT dan SUTM
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
239
5-5-2 Hantaran dan Pemasangan Saluran Udara 1. Penghantar udara yang dipakai adalah dari jenis-jenis :
a. Hantaran tak berisolasi : A2C, ABC, ACSR. b. Hantaran kabel
i. Kabel pilin TM. ii. Kabel inti tunggal (full atau halfinsulated) Dengan ukuran : 25 mm2, 50 mm2, 70mm2, 120 mm2; 150mm2, 187, 5 mm2, 240 mm2.
2. Tiang yang dipakai adalah dari jenis tiang besi, tower, beton dengan ukuran panjang 11 m, 12 m, 13 m, 15 m dan dengan kekuatan 350 daN, 500 daN, 800 daN.
3. Isolator yang dipakai adalah : - Jenis penopang PIN/PIN post/ post isolator untuk tiang tengah
Gambar 5-46 Jarak aman antara SUTR dan SUTM
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
240
- Jenis isolator penegang, umbrella lipe/model payung-piring atau - rod non puncher. - Jenis TOEI isolator untuk kawat penegang (guy wire).
4. Arrester yang dipakai adalah Type 5KA untuk pemasangan pada tiang tengah. Type 10 KA untuk pemasangan pada tiang akhir kawat.
5. Penghantar pentanahan, memakai kawat tembaga tak berisolasi minimal ukuran 35 MM2 dengan elektoda batang minimal 3 meter.
6. Peralatan bantu lain Bending wire/preformed Stainless steelstrap Uclamp, sengkang Link. Mur baut galvanized
7. Tiang ditanam sedalam 1/6 X tinggi tiang 8. Pemilihan kekuatan tiang
Besarnya kekuatan tiang dipilih berdasarkan: - Luas penampang hantaran. - Sistem jaringan ( 1 fasa, 3 asa) - Sudut belokan hantaran - Fungsi tiang (misalnya tiang seksi)
Besarnya kekuatan tiang didasarkan atas temperatur maksimum hantaran, tanpa hembusan angin
Tabel berikut ini memberikan tuntunan pemilihan besarnya kekuatan tiang.
Tabel 5-2. Pemilihan Kekuatan Tiang Ujung Jaring Distribusi Tegangan Menengah
JARAK SUDUT PENGHANTAR PENGHANTAR UKURAN TIANG (dAN) GUY KETE-
GAWANG JALUR A3C TWISTED JTM 200 350 S00 800 2X800 1200 WIRE RANGAN
5O M 0O – 15O 35 mm2 X X 15O -30O 35 mm2 X X - 30O – 60O 35 mm2 X X >60O 35 mm2 X X X 0O – 15O 70 mm2 X X 15O -30O 70 mm2 X X 30O – 60O 70 mm2 X X >60O 70 mm2 X X X - 0O – 15O 150 mm2 X X 15O -30O 150 mm2 X X 30O – 60O 150 mm2 X X X >60O 150 mm2 X X X 0O – 15O 240 mm2 X X 15O -30O 240 mm2 X X 30O – 60O 240 mm2 X X X >60O 240 mm2 X X X _ 0O – 15O Double - X 15O -30O Circuit - X 30O – 60O 150 mm2 - X X
>60O - X X
sudut
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
241
5-5-3 Kekuatan Tiang Seksi 1. Apabila terjadi perubahan luas penghantar pada satu tiang maka
besarnya tiang yang dipilih, dihitung dengan cara perubahan kekuatan tiang, diasumsikan berfungsi sebagai tiang awal masing-masing penghantar.
Contoh Penampang A3C 3 x 150 mm2 bertemu dengan A3C 3 x 35 mm2, Jarak gawang 40 meter. Berapa kekuatan tiang seksi tersebut.
Jawab: Tiang awal A3C 3 x 150 mm2 = 2 x 800 daN Tiang awal A3C 3 x 35 mm2 = 800 daN Beda kekuatan 800 daN Dipilih besar kekuatan tiang seksi 800 daN.
Sagging (lendutan) dari Jarak Gawang 2. Lendutan atau sagging menentukan besamya kekuatan tarik tiang
khususnya tiang ujung.
3. Perhitungan sederhana besarnya lendutan / sagging adalah 40 cm untuk jarak gawang 40 meter 60 cm untuk jarak gawang 50 meter 85 cm untuk jarak gawang 60 meter
dengan catatan Temperatur 20° C Kekuatan angin 50 km/jam Angka keamanan 2
4. Untuk kekuatan tiang sebagai fungsi sagging dan jarak gawang dapat dilihat pada tabel lembar berikut.
5-5-4 Konstruksi Pemasangan Isolator a. Untuk tiang lurus (line pole), memakai satu isolator Pin atau sejenis. b. Untuk tiang sudut 0° -15°, memakai satu isolator Pin atau sejenis c. Untuk tiang sudut 15° - 30° memakai dua isolator Pin atau sejenis. d. Untuk tiang sudut diatas 30° memakai dua isolator tarik dengan
cross arm minimal panjang 2200 cm. e. Untuk pemakaian isolator jenis post insulator, dapat dipakai dengan
sudut sampai dengan 15°, lebih besar dari 15° memakai 2 isolator tarik (hang isolator).
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
242
5-5-5 Konstruksi Elektroda Pembumian a. Elektroda pembumian ditanam 0,3 meter dari titik tanam tiang atau
dari sisi luar fondasi.
b. Terminal sambungan dengan penghantar pembumian disambung 0,2 meter dibawah permukaan tanah.
c. Sambungan dilakukan dengan mur baut anti korosif / anti karat.
5-5-6 Palang Sangga (Crossarm, Travers) dengan Ukuran Tertentu
a. Contoh : Panjang 240 cm untuk tiang sudut. Panjang 180 cm untuk tiang tengah lurus.
Material harus terbuat dari metal UNP 8, 15 dan digalvanisir. Contoh konstruksi PT. PLN (Persero) pada gambar lampiran
5-5-7 Ikatan Isolator pada Hantaran a. Hantaran diikat dengan isolator memakai bending wire (A3C) atau preformed. Panjang minimum bending wire ± 2 meter.
b. Agar diperhatikan tata cara mengikatnya.
5-5-8 Guy Wire (Trekskur) atau Kawat Penarik a. Guy wire dirancang untuk memungkinkan pemakaian tiang akhir
dengan kekuatan yang kecil, sejauh ruang batas memungkinkan.
b. Guy wire terbuat dad kawat baja anti karat jenis "stranded steel wire", dengan ukuran minimal 90 mml
c. Dengan memakai guy wire, besar kuat tarik tiang akhir dapat dipilih seminimal mungkin.
Contoh: Konstruksi guy wire standaro konstruksi PT. PLN (Persero).
5-5-9 Konstruksi Pole Top Switch Pole top switch memakai tiang 2 x 500 daN atau 800 daN atau 2 x 800
daN, jika berfungsi sebagai tiang seksi.
5-5-10 Konstruksi Arrester Arus pengenal Arrester pada tiang ujung, memakai arrester 10 kA. Arus pengenal pada tiang tengah, memakai arrester 5 KA
(lihat konstruksi Arrester standard konstruksi PT. PLN (Persero).
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
243
5-5-11 Konstruksi Cut Out Fused Cut Out Fused mempunyai fungsi ganda menurut sistem jarngan yang
dianut baik sebagai pengaman hubung tanah satu fasa atau sebagai pengaman hubung singkat pada gardu.
5-5-12 Konstruksi Kawat Tanah (earth wire) Konstruksi kawat tanah dipakai di daerah Jawa Timur, dipasang
di atas penghantar fasa
5-5-13 Konstruksi Saluran Udara Tegangan Menengah Sistem Multi Grounded 3 Fasa 4 Kawat
Konstruksi sistem 3 fasa 4 kawat atau disebut pentanahan netral bersama dipergunakan di daerah Jawa Tengah.
Saluran Tegangan Menengah mempunyai penghantar netral yang dijadikan satu dengan penghantar netral sisi jaringan tegangan rendah.
Konstruksi Saluran Udara sedikit berbeda dengan konstruksi 3 fasa 3 kawat (di daerah DKI Jaya, Jabar, Jatim & Luar Jawa).
5-5-14 Konstruksi-konstruksi Setempat Pada beberapa daerah (Sumsel, Lampung, dll) pemakaian model
atau ∆, masih ada.
Ketentuan pemakaiannya tergantung atas Standard setempat yang dipakai.
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
244
5-5-15 Konstruksi Jaringan Tiang SUTM
Gambar 5-47. JTM 3 fasa 20 kV Menggunakan tiang besi / beton Pin type insulator & kawat AAAC/AAAC-S per kms jarak gawang 50 meter (sistem 3 kawat)
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
245
Gambar 5-48. JTM 3 fasa 20 kV Menggunakan tiang besi / beton Pos type insulator & kawat AAAC/AAAC-S per kms jarak gawang 50 meter (sistem 3 kawat)
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
246
Gambar 5-49. JTM 3 fasa 20 kV Menggunakan tiang besi / beton dengan kabel udara Twisted 20 kV per kms jarak gawang 50 meter (sistem 3 & 4 kawat)
No Nama Material Sat. Ke but No Nama Material Sat. Ke
But.1 Twisted kabel 20 kV Km 1,1 11 Stopping buckle Bh 60 2 Tiang besi/beton 11m 200&350 daN Bt 16 12 Overhead cable junction set 20 kV Set 2 3 Tiang besi/beton 11m 500 daN Bt 5 13 Messenger compression joint Bh 50 4 Suspension assembly Set 16 14 Span guy lengkap Set 1 5 Small angle assembly Set 1 15 Down guy lengkap Set 4 6 Large angle assembly Set 6 16 Pentanahan lengkap Set 21 7 Adjustable dead end assembly Set 1 17 T. Box junction set 20 kV bh 1
8 Protective plastic tape Mtr 20 18 Cross arm UNP 100x50x6x2000 mm & U bolt Bh 2
9 Plastic strap 20x300 & 20x1000 & 20x1500 Bh 60,
4, 2 19 Cross arm UNP 100x50x6x350 mm D. Armb Bh 6
10 Stainless steel strip mtr 45 20 Plat U (Strap) 200x80x5x & bolt bh 9
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
247
Gambar 5-50. JTM 3 fasa 20 kV Menggunakan tiang besi / beton Pin type insulator & kawat AAAC / AAAC-S per kms jarak gawang 50 meter (sistem 4 kawat)
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
248
Gambar 5-51. JTM 3 fasa 20 kV Menggunakan tiang besi / beton Pos type insulator & kawat AAAC/ AAAC-S per kms jarak gawang 50 meter (sistem 4 kawat)
No Nama Material Sat Ke but
1 Kawat AAAC / AAAC-S km 4,62 Tiang beton 11m 350 daN Bt 183 Tiang beton 11m 500 daN Bt 34 Lightning Arrester 24 kV 5 kA bh 35 Suspension/Strain rod insul. 20kV
lengkap bh 18
6 Insultator 20 kV lengkap (ansi 56-3 tp Pin bh 61
No Nama Material Sat Ke but
7 Top Connector bh 18 8 Joint Sleeve bh 6 9 Cross arm UNP
100x50x6x2000 mm + U bolt Bh 17
10 Cross arm UNP 100x50x6x 2000 mm + d. arm bolt Bh 6
11 Pelat baja penahan cross arm bh 23 12 Pentanahan lengkap set 21 13 Preformed tie bh 61 14 Down guy lengkap set 3 15 Span guy lengkap set 1 16 Penghalang panjat & papan
tanda kilat bh 21 17 Strip Stainless steel mtr 3 18 Stopping buckle bh 6 19 Tap connector bimetal Al Cu bh 8 20 Isolator tarik TR bh 24 21 Dudukan Isolator tarik TR tipe
& bolt bh 5 22 Bolt U/.pemegang insulator bh 18 23 Tention clamp bh 18 24 U-bolt anchor shockle & Clevis
eye bh 18
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
249
Gambar 5-52. JTM 1 fasa 20 kV Menggunakan tiang besi/ beton Pin type insulator & kawat AAAC / AAAC-S per kms jarak gawang 50 meter
Detail 10d
No Nama Material Sat Ke but
1 Kawat AAAC / AAAC-S km 4,62 Tiang beton 11m 350 daN Bt 183 Tiang beton 11m 500 daN Bt 34 Lightning Arrester 24 kV 5 kA bh 35 Suspension/Strain rod insul.
20kV lengkap bh 18
6 Insultator 20 kV lengkap (ansi 56-3 tp Post bh 61
No Nama Material Sat Ke but
7 Tap Connector bh 18 8 Joint Sleeve bh 6 9 Cross arm UNP 100x50x6x2000
mm + U bolt Bh 17
10 Cross arm UNP 100x50x6x 2000 mm + d. arm bolt Bh 6
11 Pelat baja penahan cross arm bh 23 12 Pentanahan lengkap set 21 13 Preformed tie bh 61 14 Down guy lengkap set 3 15 Span guy lengkap set 1 16 Penghalang panjat & papan tanda
kilat bh 21 17 Strip Stainless steel mtr 3 18 Stopping buckle bh 6 19 Tap connector bimetal Al Cu bh 8 20 Isolator tarik TR bh 24 21 Dudukan Isolator tarik TR tipe
& bolt bh 5 22 Bolt U/.pemegang insulator bh 18 23 Tention clamp bh 18 24 U bolt, Anchor shockle & Clevis eye bh 18
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
250
Gambar 5-53. JTM 1 fasa 20 kV Menggunakan tiang besi/beton Post type insulator & kawat AAAC / AAAC-S per kms jarak gawang 50 meter
No Nama Material Sat Kebut1 Kawat AAAC / AAAC-S km 2,22 Tiang beton 11m 200 daN Bt 183 Tiang beton 11m 350 daN Bt 3
No Nama Material Sat Ke but
4 Lightning Arrester 24 kV 5 kA bh 1
5 Suspension/Strain rod insul. 20kV lengkap bh 12
6 Insultator 20 kV lengkap (ansi 56-3 tp Pin bh 40
7 Tap Connector bh 12 8 Joint Sleeve bh 4
9 Cross arm UNP 100x50x6x2000 mm + U bolt Bh 17
10 Cross arm UNP 100x50x6x 2000 mm + d. arm bolt Bh 6
11 Pelat baja penahan cross arm bh 23 12 Pentanahan lengkap set 21 13 Preformed tie bh 40 14 Down guy lengkap set 3 15 Span guy lengkap set 1
16 Penghalang panjat & papan tanda kilat bh 21
17 St rop Stainless steel mtr 3 18 Stopping buckle bh 6 19 Tention Clamp bh 8
20 U bolt, Anchor shockle & Clevis eye bh 24
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
251
5-5-16 Konstruksi Tiang SUTM Berikut ini adalah beberapa jenis konstruksi tiang SUTM sesuai
dengan kebutuhan lokasi di mana tiang tersebut akan dipasang, serta daftar Material Distribusi Kecil (MDK) yang diperlukan.
Konstruksi tiang penyangga Gambar 5-54, dipakai pada jaringan lurus dan jaringan dengan sudut belok maksimum 15 derajat. Konfigurasi tiang jenis TM-1 paling banyak digunakan dibandingkan konstruksi jenis lain.
Material Distribusi Kecil (MDK) untuk tiang TM-1, seperti tertera pada keterangan gambar 5-54. Konstruksi tiang penyangga ganda (TM-2) untuk jaringan dengan sudut belok 15-30o. Material Distribusi Kecil (MDK) seperti tertera pada keterangan gambar 5-55.
Keterangan Gambar 5-55: 1. Cross Arm 2000 (type tumpu) 2. Arm Tie type 750 pipe φ ¾” 3. Bolt & Nut M16x400 + Washer 4. 20 kV Pin Post Insulator + Steel Pin 5. Alluminium Binding Wire 3,2mm 6. Alluminium tape 4,0mm 7. Preformed Top Tie 240/150/70/35
Catatan: No. 5, 6 digunakan tanpa 7 No. 7 digunakan tanpa 5, 6
Gambar 5-55. Konstruksi tiang penyangga ganda (TM-2)
Kode pada gambar distribusi
Gambar 5-54. Konstruksi tiang penyangga (TM-1)
Keterangan gambar 6-54: 1. Cross Arm 2000 (type tumpu) 2. Arm Tie type 750 pipe φ ¾” 3. Bolt & Nut M16x400 + Washer 4. Bolt & Nut M16x50/M16x120+ Washer 5. 20 kV Pin Post Insulator + Steel Pin 6. Alluminium Binding Wire 3,2mm 7. Alluminium tape 4,0mm 8. Preformed Top Tie 240/150/70/35
Catatan: No. 6, 7 digunakan tanpa 8 No. 8 digunakan tanpa 6, 7
Kode pada Gambar Distribusi
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
252
Kode pada Gambar Distribusi
Konstruksi tiang tarik akhir (TM-4), sebagai tiang akhir dari suatu jaringan. Material Distribusi Kecil (MDK) seperti tertera pada keterangan gambar 5-6.
Keterangan Gambar 5-56: 1. Strain Insulator 20kV 2. Cross Arm 2000 (type tarik)
3. Arm Tie type 750 pipe φ ¾” 4. Bolt & Nut M16 x 140 + Washer (Double Arm) 5. Ball Devis + Socked Eye 6. HV Band Strap 7. Bolt & Nut M16 x 140 + Washer 8. Dead End Damp (StrainDamp)
9. U Strap
Gambar 5-56. Konstruksi tiang tarik akhir (TM-4)
Gambar 5-57. Detail rangkaian isolator tarik/gantung
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
253
Kode pada Gambar Distribusi
Gambar 5-58. Konstruksi tiang penegang (TM-5)
Keterangan Gambar 5-58: 1. 20kV Pin/pin Post Insulator + Steel Pin 2. 20kV Strain Insulator 3. Cross Arm 2000 (type tarik)
4. Arm Tie type 750 pipe φ ¾” 5. Bolt & Nut M16 x 140 + Washer 6. Susp. VEE/Croos Arm Devis/Band Strap 7. Ball Devis & Socked Eye 8. Dead and Damp/Preformed Term + Thimble 9. Bolt & Nut M16x400 + Washer (double Arm)
10. U Strap 11. Alluminium Binding Wire 3,2 mm 12. Alluminium tape 4,0 mm
13. Preformed Top Tie 240/150/70/35 14. Line Tap Connector Keterangan : No. 11, 12 digunakan tanpa No. 13 No. 13 digunakan tanpa No. 11 & 12
Gambar 5-59.Konstruksi tiang penegang dengan Cut Out Switch pada tiang akhir lama (TM-4XC)
Keterangan Gambar 5-59: 1. Cross Arm 2000 (type tarik) 2. Bolt & Nut M16 x 140 + Washer (Double Arm) 3. Double Arm Band & Nut + Washer
4. Arm Tie type 750 pipe φ ¾” 5. Arm Tie Band + Bolt & Nut M.16 x 50 6. Bolt & Nut M140 + Washer 7. 20kV Strain Insulator 8. Strain Clamp / Preformet Tem. 9. Ball Clevis & Socked Eye
10. Cross Arm Clevis / HV Band Strap 11. Terminal Lug Cu / Al 12. Cut Out Switch 22 kV-100 A + Bracket 13. Fuse Link 100A
Kode pada Gambar Distribusi
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
254
Konstruksi tiang tarik ganda (TM-5) dipasang di setiap panjang jaringan lurus 500-700 meter. Material Distribusi Kecil (MDK) untuk SUTM ini seperti tertera pada keterangan gambar 5-10.
Gambar 5-60.Konstruksi tiang tarik ganda (TM-5)
Keterangan Gambar 5-60: 1. 20kV Pin/Pin Post Insulator + Steel Pin 2. 20kV Strain Insulator 3. Cross Arm 2000 (type tarik) 4. Arm Tie type 750 (pipe φ ¾”) 5. Bolt & Nut M16 x 140 + Washer 6. Susp. VEE/Croos Arm Clevis/Band Strap 7. Ball Clevis & Socked Eye 8. Dead and Clamp/Preformed Term +
Thimble 9. Bolt & Nut M16x400 + Washer(Double Arm)
10. U Strap 11. Alluminium Binding Wire 3,2 mm
Kode pada Gambar Distribusi
12. Alluminium tape 4,0 mm 13. Preformed Top Tie 240/150/70/35
14. Line Tap Connector Catatan: No. 11 & 12 Digunakan tanpa No.13 No. 13 Digunakan tanpa No.11, 12
Gambar 5-61. Konstruksi penegang dengan
Cut Out Switch (TM5C)
Kode pada Gambar Distribusi
9. U Strap 10. String / Tension Disc. Insulator 20kV 11. Double Arm Band + Bolt & Nut + Washer 12. Cut Out Switch 22 kV+Fuse Link 100 A
Keterangan Gambar 5-61: 1. Cross Arm 2000 NP 10/Square pipe (tarik) 2. Double Bolt & Nut M16x400/500+ Washer 3. Arm Tie type 750 (pipe φ ¾”) 4. Arm Tie Band & Nut M16x50 + Washer 5. Strain Damp/ Preformed Term + Thimble 6. Ball Devis & Socked Eye 7. Croos Arm Devis/ Susp. VEE/ Band Strap 8. Bolt & Nut M16 x 140 + Washer
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
255
Konstruksi penegang dengan Cut Out Switch (TM5C), maksudnya pada konduktor penghubung antara dua strain dipasang cut out switch, sehingga dapat digunakan sebagai pemisah rangkaian bila terjadi gangguan atau untuk pemeliharaan.
Kode pada Gambar Distribusi
Gambar 5-62. Konstruksi Percabangan tiang
penyangga dan tarik (TM8)
Kode pada Gambar Distribusi Gambar 5-63. Konstruksi
Tiang sudut (TM10)
Keterangan Gambar 5-62: 1. 20kV Pin/Pin Post Insulator + Steel Pin 10. Bolt & Nut M140 + Washer
2. Cross Arm type-2000 (tumpu) 11. Double Arm Band + Bolt & Nut + Washer 3. Bolt & Nut M16x400/500 + Washer (Double Arm) 12. Cross Arm type 2000 (tarik) 4. Arm Tie type 750 pipe φ ¾” 13. Dead and Damp/Preformed Termination
5. Arm Tie Band, Nut, Washer 14. Alluminium Binding Wire 3,2mm 6. U Strap 15. Alluminium tape 4,0mm
7. Tension Disc./ String Insulator 20kV 16. Preformed Top Tie 240/150/70/35 Sqmm 8. Ball Devis & Socked Eye 17. Line Tap Connector
9. Susp.VEE/Croos Arm Devis/Band Strap
Keterangan Gambar 5-63: 1. 20kV Pin/Pin Post Insulator + Steel Pin 11. Double Arm Band + Bolt & Nut + Washer 2. Tension Disc./ String Insulator 20kV 12. Dead end/Strain Damp/Preformed Term.
3. Bolt & Nut M16x500 + Washer(Double Arm) 13. Alluminium Binding Wire 3,2mm 4. Arm Tie type 750 pipe φ ¾” 14. Alluminium tape 4,0mm
5. Arm Tie Band, Nut M16 + Washer 15. Preformed Top Tie 240/150/70/35 Sqmm 6. U Strap 16. Line Tap Connector/HH connector
7. Cross Arm type -2000 (tarik) 8. Ball Devis & Socked Eye Catatan: 9. Band Strap/Croos Arm Devis/Susp. VEE No. 13, 14 Digunakan tanpa No.15 10. Bolt & Nut M16 x 140 + Washer No. 15 Digunakan tanpa No.13, 14
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
256
Keterangan Gambar 5-64: 1. Cross Arm 2000 (type tarik) 2. Double Bolt & Nut M16x400/500+ Washer 3. Double Arm Band + Nut & Washer 4. Arm Tie type 750 pipe φ ¾” 5. Arm Tie Band Bolt + Nut M16 + Washer 6. Bolt & Nut M16 x 140 + Washer 7. 20kV Strain Insulator 8. Strain Damp 9. Ball Devis & Socked Eye 10. Croos Arm Devis 11. U Strap 12. Cut Out Switch 22 kV/100 A + Fuse 8A +
Bracket 13. 20kV Pin/Pin Post Insulator + Steel Pin 14. Alluminium Binding Wire 3,2mm 15. Alluminium tape 4,0mm
16. Preformed Top Tie 240/150/70/35 Sqmm 17. Terminal Lug 150-Cu/Al
Catatan: No. 14, 15 Digunakan tanpa No.16 No. 16 Digunakan tanpa No.14, 15
Dengan konstruksi percabangan tiang penyangga dan tarik, diperlukan dua buah cross arm, yaitu satu cross arm tumpu untuk penghantar yang lurus, dan dua cross arm tarik untuk penghantar cabang. Untuk konstruksi tiang sudut diperlukan dua set Cross arm tarik dan kelengkapannya, serta dua atau tiga isolator Pin untuk penghantar penghubung.
Gambar 5-64. Konstruksi tiang sudut dilengkapi Cut Out Switch (TM10C)
Kode pada Gambar Distribusi
Konstruksi portal dua tiang diperuntukkan pada jaringan yang memer-lukan gawang lebih jauh dari jarak maksimum yang diijinkan untuk jaringan normal. Misalnya SUTM yang ditarik diatas sungai, terletak disampingnya jembatan pada sungai yang lebar. Untuk konstruksi ini diperlukan cross arm 3000 type tarik, dan perlengkapan yang lain disesuaikan seperti tertera pada keterangan gambar 5-15.
Keterangan Gambar 5-65: 1. Cross Arm 3000 (Square pipe/Np 10) type
tarik 2. Arm Tie type 750 pipe φ ¾” 3. 20kV Pin/Pin Post Insulator + Steel Pin 4. 20kV Tension Disc/Strain Insulator 5. Double Arm Bolt & Nut M16x400+Washer 6. Bolt & Nut M16 x 140 + Washer 7. HV Band Strap/Susp.VEE/Croos Arm
Devis 8. Ball Devis & Socked Eye 9. HV Dead end Damp/Preformed
Termination 10. Double Arm Band + Nut & Washer 11. Arm Tie Band + Nut M16 & Washer 12. Alluminium Binding Wire 3,2mm 13. Alluminium tape 4,0mm 14. Preformed Top Tie 240/150/70/35 Sqmm 15. Line Tap Connector Catatan: No. 12 & 13 Digunakan tanpa No.14 No. 14 Digunakan tanpa No.12, 13
Gambar 5-65. Konstruksi portal dua tiang (TMTP2)
Kode pada Gambar Distribusi
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
257
Konstruksi portal tiga tiang diperuntukkan pada jaringan yang memerlukan gawang lebih jauh dari konstruksi portal dua tiang. Untuk konstruksi ini diperlukan cross arm 6000 type tarik, dan perlengkapan yang lain disesuaikan seperti tertera pada keterangan gambar 5-66.
Keterangan Gambar 5-66:1. Cross Arm 6000 (Square pipe/Np 10) type tarik 2. Arm Tie type 900 pipe φ ¾” 3. 20kV Pin/Pin Post Insulator + Steel Pin 4. 20kV Tension Disc./ Strain Insulator 5. Double Arm Bolt & Nut M16x400 + Washer 6. Bolt & Nut M16x140 + Washer 7. HV Band Strap/Susp.VEE/Croos Arm Devis
Gambar 5-66 Konstruksi portal tiga tiang (TMTP3)
Kode pada Gambar Distribusi
8. Ball Devis & Socked Eye 9. HV Dead end Damp/Preformed Termination 10. Double Arm Band + Nut & Washer 11. Arm Tie Band + Nut M16 & Washer 12. Alluminium Binding Wire 3,2mm 13. Alluminium tape 4,0mm 14. Preformed Top Tie 240/150/70/35 Sqmm 15. Line Tap Connector 240/150/70/35 Sqmm Catatan: No. 12 & 13 Digunakan tanpa No.14 No. 14 Digunakan tanpa No.12, 13
8. HV Band Strap/Susp.VEE/Croos Arm Devis 9. Ball Devis & Socked Eye
10. HV Dead end Damp/Preformed Term 11. Double Arm Band + Nut & Washer 12. Arm Tie Band + Nut & Washer 13. Alluminium Binding Wire 3,2mm 14. Alluminium tape 4,0mm 15. Preformed Top Tie 150/70/35 Sqmm 16. Line Tap Connector 240/150/70/35 Sqmm 17. Cross Arm 3000 (Square pipe/Np 10) type
tarik Catatan: No. 13 & 14 Digunakan tanpa No.15 No. 15 Digunakan tanpa No.13 &14
Keterangan Gambar 5-67: 1. Cross Arm 3000 (Square pipe/Np 10) type
tarik 2. Arm Tie type 900 pipe φ ¾” 3. Arm Tie type 750 pipe φ ¾” 4. 20kV Pin/Pin Post Insulator + Steel Pin 5. 20kV Tension Disc/Strain Insulator 6. Double Arm Bolt & Nut M16x400/500 +
Washer 7. Bolt & Nut M16 x 140 + Washer
Kode pada Gambar Distribusi
Gambar 5-67. Konstruksi sudut portal dua tiang (TMTP2A)
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
258
Kode pada Gambar Distribusi
Konstruksi sudut portal tiga tiang (TMTP3A) secara teknik hampir sama dengan konstruksi sudut portal dua tiang, yaitu merupakan kombinasi antara konstruksi portal dengan tarikan tiang akhir jaringan. Untuk tarikan tiang akhir bisa dari arah samping (konstruksi sudut) atau lurus dengan tarikan portal. Dalam hal ini tinggal melengkapi dengan guy wire atau strut pole.
Keterangan Gambar 5-68: 1. Cross Arm 6000 (Square pipe/Np10) type tarik 2. Arm Tie type 900 pipe φ ¾” 3. 20kV Pin/Pin Post Insulator + Steel Pin 4. 20kV Tension Disc/Strain Insulator 5. Double Arm Bolt & Nut M16x400/500+Washer 6. Bolt & Nut M16 x 140 + Washer 7. HV Band Strap/Susp.VEE/Croos Arm Devis 8. Ball Devis & Socked Eye 9. HV Dead end Damp/Preformed Termination 2
10. Double Arm Band + Nut & Washer 11. Arm Tie Band + Nut M16 & Washer 12. Alluminium Binding Wire 3,2mm 13. Alluminium tape 4,0mm
Gambar 5-68. Konstruksi sudut portal tiga tiang (TMTP3A)
Kode pada Gambar Distribusi
14. Preformed Top Tie 240/150/70/35 Sqmm 15. Line Tap Connector 240/150/70/35 Sqmm 16. Arm Tie type 750 pipe φ ¾” 17. Cross Arm 2000 (Square pipe/Np10) type tarik
Catatan: No. 12 & 13 Digunakan tanpa No.14 No. 14 Digunakan tanpa No.12, 13
Gambar 5-69. Konstruksi tiang akhir dengan pemasangan kabel tanah (TM11)
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
259
Guy Wire diperlukan untuk konstruksi tiang akhir, dan lokasi (lahan) penempatan guy wire itu ada (tidak bermasalah). Jika tidak dimungkinkan ada-nya lahan, maka dapat di-pasang guy wire dengan stut di tengah tiang, jadi jarak antara tiang dengan beton blok lebih pendek. Yang perlu diperhatikan dalam pemasangan guy wire adalah besar sudut kemiringannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena secara teknik hal ini menyangkut posisi tiang, dimana tiang harus bisa berdiri tegak. Jika sudut lebih kecil, maka tiang akan melengkung dan bisa patah.
Keterangan Gambar 5-69: 1. Strain / Tension Disc Insulator 20kV 2. Cross Arm 2000 (Square pipe/Np10) type tarik
3. Double Arm Band + Nut M16x400 + Washer 4. Arm Tie type 750 pipe φ ¾”
5. Arm Tie Band + Nut M16 & Washer 6. Double Arm Bolt + Nut & Washer 7. U Strap 8. HV Band Strap/Croos Arm Devis /Susp.VEE 9. Ball Devis & Socked Eye
Konstruksi tiang akhir dengan pemasangan kabel tanah (TM11), diperlukan pada jaringan yang akan dihubungkan dengan gardu beton atau gardu besi, dan pada jaringan yang akan melintas di bawah jaringan tegangan tinggi. Model yang ke dua ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya interferensi magnetik dengan saluran diatasnya.
10. Dead end/Strain Damp/Preformed Termination + Thible
11. Bolt & Nut M16 x 140 + Washer 12. Lightning Arrester 20kV 13. Mounting Breaket for Arrester 14. Cable band + Nut & Waster 15. Copper Tube / Cable Schoen 16. PDC. 8 mm/ MV Insulated Conductor (Cu) 17. Jumper wire 80 mm / MV Conductor
Keterangan Gambar 5-70: 1. Guy Wire Band + Bolt & Nut M16 x 50 2. Turn Buckle 3. Preformet Grip 22/35/55/70 Sqmm 4. Guy Insulator 5. Galv. Steel Stranded Wire 22/35/55/70 6. Wire Dip 7. Pipa pelindung ¾” – 2mtr 8. Guy Rod 2,5 Mtr 9. Guy Rod 1,8 Mtr
10. U Bolt & Nut M 16 11. Anchor Block 500 x 500 mm 12. Expanding Anchor 13. Span Schroef 5/8”
Keterangan Type Tiang
Galv. Steel Stranded Wire (X)
11 Mtr 13 Mtr9 Mtr 11 Mtr7 Mtr 9 Mtr
45o-60o
Gambar 5-70. Konstruksi Guy Wire (GW)
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
260
No.Type Tiang Satuan dalam meter
Utama Strut Pole A B C D E
1 11 11 8,4 10 5,42 1,83 1 2 11 9 7,7 8,4 3,3 1,83 0,6 3 9 9 6,75 8 4,2 1,5 1 4 7 7 5,3 6,5 3,7 1,16 0,5
Gambar 5-71. Strut Pole (SP)
TIANG UTAMA
HANTARAN AAAC 3X(SQM) 35 70 150 240
11-350 9-200 9-200 9-200 11.200 11-200 9-200 9-200 11.200 9-200 7-100 9-100
No. Nama Material 1. Strut Arm Band + Bolt & Nut M 16x50 2. Strut Arm 3. Pipa Galvaniz φ 2” – 1,5 Mtr 4. Single GW Band + Bolt & Nut M 16x75 5. Bolt & Nut M 16 x 75
Konstruksi Strut pole dipasang, jika pada lokasi tersebut tidak bisa dipasang guy wire. Letak strut pole berlawanan dengan guy wire, maksudnya posisi strut pole berada di bawah tarikan penghantar, sedang guy wire di luar penghantar(arah berlawanan).
Harga strut pole jauh lebih mahal daripada harga guy wire. Pemasangan strut pole tidak hanya di ujung, tetapi bisa di percabangan di tengah saluran, atau pada lokasi yang membutuhkan kekuatan mekanis cukup tinggi dan sangat strategis.
Pemasangan Horizontal Guy Wire diperlukan jika pada lokasi tersebut tidak bisa di pasang guy wire, misalnya terhalang sungai atau jalan raya.
Keterangan: Type tiang Galv. Steel Stranded Wire (X) TM-9 Mtr 30 Mtr TR-9/7 Mtr 28 Mtr
Keterangan Gambar 5-20: 1. Guy Wire Band + Bolt & Nut M16 x 50 2. Turn Buckle 3. Preformet Grip 22/35/55/70 Sqmm 4. Guy Insulator 5. Galv. Steel Stranded Wire 22/35/55/70 6. Wire Dip 7. Pipa pelindung ¾” – 2mtr 8. Guy Rod 2,5 Mtr 9. U Bolt & Nut M 16
10. Anchor Block 500 x 500 mm 11. Expanding Anchor 12. Span Schroef 5/8” 13. Guy Rod 1,8 Mtr
Gambar 5-72. Horizontal Guy Wire (HGW) No. 11 dipasang sebagai pengganti No. 8, 9,10,13
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
261
5-6 Konstruksi Palang Sangga (Cross Arm, Travers) Berkaitan dengan arah tarikan kawat yang harus mengikuti arah jalan (raya), apakah lajur lurus atau berbelok dalam beberapa derajat, maka diperlukan palang sangga sesuai dengan kebutuhan perlengkapan dalam pemasangan Saluran Udara Tegangan Menengah. Berikut ini adalah beberapa model/bentuk palang sangga pada jaring SUTM.
Gambar 5-73. Pemasangan Cross Arm double Tumpu pada Tiang Beton Bulat
No. Kode Jml Jenis Material1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11
tb a-1 c j
bkp stp e-1 e
stp g h
1 bt 2 bh 4 bh 2 bh 2 bh 4 bh
12 bh 4 bh 4 bh 6 set 6 bh
Tiang beton bulat Cross Arm UNP 10 100.50.5 x 2000 mm Klem beugel type II 50x6 mm Double arming boll 5/8” x 300 mm Arm tie broce 50.50 x 1270 mm Steel plat type I Mur baut spring washer 5/8” x 148 mm Mur baut spring washer 5/8” x 70 mm Steel plat type II Isolator tumpu type post Double side ties
TAMPAK ATAS
TAMPAK DEPAN
POTONGAN A - A
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
262
TAMPAK ATAS
TAMPAK DEPAN
POTONGAN A-A
No. Kode Jml Jenis Material 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11
tb a-1 c
stp bkp e
e-1 stp g h
e-1
1 bt 2 bh 2 bh 4 bh 2 bh 4 bh
12 bh 4 bh 6 set 6 bh 1 bh
Tiang beton type H Cross Arm UNP 10 100.50.5 x 2000 mm Klem beugel type II tiang H Double arming boll 5/8” x 300 mm Arm tie broce 50.50 x 1270 mm Mur baut spring washer 5/8” x 70 mm Mur baut spring washer 5/8” x 148 mm Steel plat type II Isolator tumpu type post Prilarm double side ties Klem beugel type I tiang H
Gambar 5-74 Pemasangan Cross Arm double Tumpu pada Tiang Beton H
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
263
Gambar 5-75. Pemasangan Cross Arm Tention Support 2000 mm pada Tiang Beton Bulat
TAMPAK ATAS
No. Kode Jml Jenis Material1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11
tb a-1 c j
bkp stp e-1 e
stp g h
1 bt2 bh4 bh2 bh2 bh4 bh
12 bh4 bh4 bh6 set6 bh
Tiang beton bulat Cross Arm UNP 10 100.50.5 x 2000 mm Klem beugel type II 50x6 mm Double arming boll 5/8” x 300 mm Arm tie broce 50.50 x 1270 mm Steel plat type I Mur baut spring washer 5/8” x 148 mm Mur baut spring washer 5/8” x 70 mm Steel plat type II Isolator tumpu type post Double side ties
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
264
No. Kode Jml Jenis Material 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13
tb a-1 bkp
c j
c-1 e-1 k l g ml prt
pil/tjn
1 bt2 bh 2 bh 4 bh 2 bh 4 bh
10 bh 4 bh 4 bh 1 bh 6 set 1 bh 6 bh
Tiang beton bulatCross Arm UNP 10 100.50.5 x 2000 mm Arm tie broce 50.50 x 1270 mm Klem beugel type II tiang beton bulat Double arming boll 5/8” x 300 mm Klem beugel type II tiang beton bulat Mur baut dan ring 5/8” x 148 mm Steel plat type I Steel plat type II Isolator tumpu type post Isolator penegang/afspan long rod Prilarm lop ties Paralel groove/non tension joint
Gambar 5-76. Pemasangan Cross Arm Tention Support 2000 mm pada Tiang Beton H
TAMPAK ATAS
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
265
Gambar 5-77. Pemasangan Cross Arm Tention Support 2200 mm Double Pole pada Tiang Beton Bulat
TAMPAK ATAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
tb a-2 c-1
j stp e-1 g h ml
pil/tjn
2 bt 2 bh 4 bh 4 bh 6 bh 6 bh
3 set 3 bh 6 set 6 bh
Tiang beton bulatCross Arm UNP 10 100.50.5 x 2200 mm Klem beugel type II tiang beton bulat Double arming boll 5/8” x 300 mm Steel plat type II Mur baut spring washer 5/8” x 148 mm Isolator tumpu type post Prilarm lop ties Isolator tarik Paralel groove/non tension joint
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
266
No. Kode Jml Jenis Material 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
tb a-2 stp c e
e-1 g h ml
pil/tjn
2 bt 2 bh 6 bh 4 bh 8 bh 6 bh
3 set 3 bh 6 set 6 bh
Tiang beton HCross Arm UNP 10 100.50.5 x 2200 mm Steel plat type II Klem beugel type II tiang beton H Mur baut dan ring 5/8” x 70 mm Mur baut spring washer 5/8” x 148 mm Isolator tumpu type post Prilarm lop ties Isolator tarik Paralel groove/non tension joint
Gambar 5-78. Pemasangan Cross Arm Tention Support 2200 mm Double Pole pada Tiang Beton H
TAMPAK ATAS
TAMPAK DEPAN
POTONGAN A-A
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
267
Gambar 5-79. Pemasangan 2 X Tention Support 2200 mm Diatas Dua Tiang
No. Kode Jml Jenis Material 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
tb a-2 c-1
j stp e-1 g h ml
pil/tjn
2 bt4 bh 4 bh 8 bh
12 bh 12 bh
6 set 6 bh
12 set 12 bh
Tiang beton HCross Arm UNP 10 100.50.5 x 2200 mm Klem beugel type II Double arming boll 5/8” x 300 mm Steel plat type II Mur baut spring washer 5/8” x 148 mm Isolator tumpu type post Prilarm lop ties Isolator tarik Paralel groove
POTONGAN A-A
TAMPAK ATAS
TAMPAK DEPAN
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
268
TAMPAK ATAS
TAMPAK DEPAN
POTONGAN A - A
No. Kode Jml Jenis Material 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
tb a-2 c e
stp e-1 g h ml
pil/tjn
2 bt4 bh 8 bh
16 bh 12 bh 12 bh
6 set 6 bh
12 set 12 bh
Tiang beton type HCross Arm UNP 10 100.50.5 x 2200 mm Klem beugel type I tiang H Mur baut dan ring 5/8” x 70 mm Steel plat type II Mur baut spring washer 5/8” x 148 mm Isolator tumpu type post Prilarm lop ties Isolator tarik Paralel groove
Gambar 5-80. Pemasangan 2 X Tention Support 2200 mm Diatas Dua Tiang Beton H
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
269
Gambar 5-81. Pemasangan 2 X ½ Tention Support 2000 mm pada Tiang Beton Bulat sudut ± 90o
No. Kode Jml Jenis Material 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12
tb a-1
j c-1 stp stp e-1 bkp g h ml
pil/tjn
1 bt4 bh 4 bh 4 bh 4 bh 8 bh
16 set 4 bh 1 set 1 bh 5 set 8 bh
Tiang beton bulat Cross Arm UNP 10 100.50.5 x 2.000 mm Double arming boll 5/8” x 300 mm Klem beugel type II 50 x 6 mm Steel plat type I Steel plat type II Mur baut spring washer 5/8” x 148 mm Arm tie broce 50.50 x 1270 mm Isolator tumpu type post Side ties Isolator tarik Paralel groove
TAMPAK ATAS
TAMPAK DEPAN
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
270
No. Kode Jml Jenis Material 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13
tb a-1 e c
stp stp e-1 bkp g h ml
pil/tjn c-1
1 bt4 bh 8 bh 4 bh 4 bh 8 bh
16 bh 4 bh 1 set 1 bh 5 set 8 bh 2 bh
Tiang beton H Cross Arm UNP 10 100.50.5 x 2.000 mm Mur baut spring washer 5/8” x 70 mm Klem beugel type I tiang H Steel plat type I Steel plat type II Mur baut spring washer 5/8” x 148 mm Arm tie broce 50.50 x 1270 mm Isolator tumpu type post Side ties Isolator tarik Paralel groove Klem beugel type II tiang H
Gambar 5-82. Pemasangan 2 X ½ Tention Support 2000 mm pada Tiang Beton H sudut ± 90o
TAMPAK ATAS
TAMPAK DEPAN
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
271
Gambar 5-83. Pemasangan Cross Arm 2 x T- Off pada Tiang Beton bulat
No. Kode Jml Jenis Material 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15
tb a-1 a c
c-1 stp e
bkp e-1 stp g ml pll h
h-1
1 bt2 bh 1 bh 2 bh 1 bh 6 bh
10 bh 4 bh
12 bh 4 bh 5 set 6 set
16 bh 3 bh 2 bh
Tiang beton HCross Arm UNP 10 100.50.5 x 2.000 mm Cross Arm UNP 10 100.50.5 x 1.800 mm Klem beugel type II untuk tiang beton Klem beugel type I untuk tiang beton Steel plat type I Mur baut dan ring 5/8” x 70 mm Arm tie brace 50.50 x 1270 mm Mur baut dan ring 5/8” x 148 mm Steel plat type II Isolator tumpu type post Isolator penegang/afspan long rod Paralel groove Performed top ties Performed side ties
TAMPAK ATAS
TAMPAK DEPAN
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
272
5-7 Telekomunikasi untuk Industri Tenaga Listrik
5-7-1 Kelasifikasi Yang termasuk dalam telekomunikasi untuk industri tenaga listrik
adalah semua fasilitas telekomunikasi yang diperlukan dalam pengelolaan perusahaan tenaga listrik, diantaranya yang menyangkut penyediaan dan kebutuhan, operasi, pengamanan dan pemeliharaan. Jaringan telekomunikasi ini merupakan sistem syaraf dalam pengelolaan perusahaan. Makin maju perusahaannya makin penting adanya fasilitas yang dapat diandalkan dan komunikasi yang cepat.
Sistem telekomunikasi ini dapat dibagi menjadi komunikasi untuk pembagian beban (load-dispatching), untuk pemeliharaan dan untuk keperluan-keperluan administratip.
5-7-1-1 Komunikasi untuk Pembagian Beban Komunikasi untuk pembagian beban digunakan untuk
memungkinkan pembagian beban secara cepat dan tidak terganggu. Oleh karena pentingnya telekomunikasi untuk tugas ini, maka sistemnya tidak boleh digunakan bersama dengan keperluan lain. Malahan, perlu diadakan pula sistem cadangan.
Dalam keadaan gangguan pada sistem tenaga, bencana alam atau bencana-bencana lainnya, sistem telekomunikasi harus tetap dapat bekerja dengan sempurna.
Fasilitas telekomunikasi yang sesuai untuk pembagian beban adalah komunikasi radio, telekomunikasi lewat pembawa PLC, dsb.
5-7-1-2 Komunikasi untuk Pemeliharaan Komunikasi untuk pemeliharaan dimaksudkan guna komunikasi
antara pusat listrik (piket distribusi), gardu distribusi, saluran distribusi, dan lain-lain. Untuk itu biasanya digunakan telekomunikasi dengan kawat bagi sistem tenaga yang kecil serta telekomunikasi dengan radio atau dengan pembawa saluran tenaga (PLC) bagi sistem tenaga yang besar. Komunikasi radio mobil sangat berguna dalam pemeliharaan saluran distribusi.
5-7-1-3 Komunikasi untuk Keperluan Administratip Komunikasi untuk keperluan administratip digunakan dalam
perhubungan antara kantor pusat, kantor daerah dan kantor cabang. Sering kali saluran komunikasi untuk pemeliharaan digunakan juga untuk keperluan administratip. Kadang-kadang yang dipakai untuk keperluan terakhir ini adalah saluran komunikasi cadangan guna tugas-tugas tersebut terdahulu.
5-7-1-4 Jenis Fasilitas
Jenis-jenis fasilitas telekomunikasi untuk industri tenaga listrik dapat dilihat pada diagram Tabel 5-3, halaman 273.
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
273
Tabel 5-3 lihat lampiran khusus tabel landscape
di halaman 275
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
274
5-7-2 Komunikasi dengan Kawat 5-7-2-1 Saluran Telekomunikasi
Komunikasi dengan menggunakan kawat tidak sesuai untuk pemakaian pada rangkaian yang penting atau yang jaraknya jauh, karena pengaruh yang besar dari angin ribut, taufan, banjir, interferensi dari saluran tenaga, dsb. terhadap kawat komunikasi ini. Meskipun demikian, komunikasi jenis ini masih dipakai pada jarak pendek karena pertimbangan ekonomis.
Komunikasi dengan kabel dipakai karena stabilitasnya lebih terjamin dibandingkan dengan komunikasi lewat saluran udara. Kerugiannya adalah bahwa komunikasi dengan kabel lebih mahal dan lebih menyulitkan apabila terjadi kerusakan.
Saluran udara dapat dipasang pada tiang-tiang yang khusus diperuntukkan baginya dan dapat pula dipasang pada tiang-tiang yang juga dipakai untuk keperluan lain, misalnya tiang distribusi. Yang terakhir ini tentu saja lebih murah.
Saluran telpon yang dipasang pada tiang saluran tenaga biasanya kabel, karena karakteristik listriknya lebih baik, lagi pula lebih kuat. Beberapa keterangan mengenai kabel telekomunikasi tertera pada Tabel 5-4.
5-7-2-2. Sistem Transmisi Komunikasi dengan kawat terdiri dari dua sistem, yakni sistem
transmisi suara dan sistem transmisi pembawa. Yang pertama menyalurkan arus untuk komunikasi sesuai dengan frekuensi suara, sedang yang kedua menyalurkannya sesudah merubah frekuensi suara menjadi frekuensi gelombang-pembawa. Biasanya daerah frekuensi untuk komunikasi pembawa adalah 3 - 60 kHz dengan jumlah saluran bicara 1-3.
Untuk komunikasi pembawa dapat dipakai saluran udara maupun kabel. Namun dalam industri tenaga listrik komunikasi dengan pembawa PLC dan komunikasi radio lebih digemari.
5-7-3 Komunikasi dengan Pembawa Saluran Tenaga Telekomunikasi dengan pembawa saluran tenaga (power line carrier,
disingkat PLC) adalah komunikasi dimana arus pembawa (carrier current) ditumpukkan (superposed) pada saluran transmisi tenaga, sehingga saluran tenaga ini menjadi rangkaian transmisi frekuensi tinggi. Jangkau frekuensinya berbeda untuk setiap negara, namun kebesarannya kira-kira berkisar antara beberapa puluh sampai 500 kHz.
Untuk memungkinkan komunikasi dengan cara ini secara effisien, yaitu dimana karakteristik penyaluran isyarat lewat pembawa digabungkan dengan karakteristik penyaluran tenaga pada tegangan tinggi, diperlukan peralatan pengait (line coupling equipment).
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
275
5-7-3-1 Peralatan Pengait Sistem pengaitan (coupling system) diklasifikasikan menurut pengaitan induktip dan pengaitan kapasitip. Karena jebakan saluran (line trap) merupakan impedansi tinggi terhadap frekuensi pembawa, maka jebakan ini diserikan dengan saluran transmisi tenaga guna memperbaiki karakteristik penyaluran gelombang-gelombang pembawa.
Pengaitan induktip lewat udara menggunakan penghantar yang dipasang sejajar dan dengan jarak tertentu dari saluran transmisi; sistem ini dipakai untuk mengaitkan peralatan PLC dengan saluran transmisi pada frekuensi tinggi. Sistem ini sekarang jarang digunakan.
Tabel 5-4. Karakteristik dan Struktur Kabel Telekomunikasi (a) Karakteristik Listrik Hal KarakteristikTahanan Isolasi Di atas 10.000 MΩ/kmTahanan Penghantar Di bawah 20,7 Ω/km (Templeratur 20OC Antara Penghantar AC 3.000 V untuk 1 menit Tegangan Dalam dan LuarKetahanan (Withstand) Antara Penghantar AC 6.000 V untuk 1 menit Luar dan Kulit LuarImpedansi Karakteristik Antara '75 (+ 5 dan/atau -1) Ω Attenuasi Di bawah 3,7 dB/kmTahanan Penghantar Di bawah 29,0 Ω/kmTahanan Isolasi Di atas 10.000 MΩ/kmKapasitansi Elektrostatik Di bawah 50 mµF/km Antara Penghantar AC 2.000 V untuk I menit Antara Penghantar
dan Tanah AC 4.000 V untuk I menit (tanpa Perisaian) Tegangan Antara Penghantar AC 2.000 V untuk I menit Ketahanan dan Perisai(Withstand) Antara Perisai dan AC 4.000 V untuk 1 menit Tanah Antara Kawat AC 1.000 V untuk I menit Penolong dan Tanah Impedansi 1 KHz 450 (Standar)Karakteristik 10 KHz 150 (Standar)(Ω) 30 KHz 130 (Standar) 1 K.Hz 0,75 (Standar)Attenuasi 10 KHz 1,7 (Standar)(dB/km) 30 KHz 2,2 (Standar)
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
276
(b) Struktur Kabel P VC
Jumlah Pasangan
Diameter Luardari Penghantar
(mm)
Tebal IsolasiPolyethylene
(mm)
Tebal VinylSheath (mm)
Diameter Luar (mm)
Berat Kira-kira kg/km
5 10 15 20 30 50
0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
2,0 2,0 2,0 2,1 2,3 2,5
14 18 20 23 27 34
240 335 455 570 820
1.220
(c) Struktur Kabel Koaksial Frekuensi Tinggi untuk Pembawa (PLC)
Hal Standar Penghantar Dalam
Material Soft copper berlilit Diameter Luar Kira-kira 1,2 mm (7/0,4 mm)
Isolasi Material Polyethylene (filled type) Tebal Kira-kira 3 mm Diameter Luar Standar 7,3 mm
Penghantar Luar Material Soft copper wire braid
Sarung Vinyl (sheath) Tebal Standar 2,5 mm
Diameter Luar Standar 13.2 mm Maksimum 14 mm
Berat Kira-kira 220 kg/km
Gambar 5-84. Peralatan Pengait untuk komunikasi Pembawa (PLC)
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
277
Ada dua jenis pengaitan dengan kapasitor. Yang pertama adalah sistem pengaitan dengan kapasitor jenis penala (tuning type), dimana rangkaian penala (termasuk kapasitor pengait) dikaitkan secara seri dengan saluran transmisi. Macam yang kedua adalah sistem pengaitan dengan kapasitor jenis penyaring (filter), dimana pengaitan peralatan PLC dengan saluran dilakukan melalui penyaring pengait dan kapasitor pengait Sistem kedua ini sekarang banyak dipakai, lihat gambar 5-87.
Kapasitor pengait memisahkan saluran transmisi dari peralatan PLC dan bersama penyaring pengait merupakan jaringan empat-kutub yang meneruskan frekuensi tinggi. Yang dipakai biasanya adalah kapasitor kertas terisi minyak seperti terlihat pada Gambar -88, dengan kapasitansi elektrostatis 0,001 - 0,002 µF.
Sebagai penyaring dipakai "band-pass filter". Rangkaiannya dari jenis trafo seperti terlihat pada Gambar 5-87(b). Ruginya dalam daerah frekuensi yang diteruskan (passing band) 1 - 1,5 dB ke bawah.
Jebakan saluran terdiri dari kumparan utama yang meneruskan frekuensi niaga, alat penala yang memberikan impeclansi frekuensi tinggi yang dikehendaki serta arester yang melindungi peralatan. Contoh
rangkaiannya dapat dilihat pada Gambar 5-87 dan Gambar 5-88. Induktansi kumparan utamanya kira-kira 0, 1 -1 mH, sedang impedansi frekuensi tingginya mempunyai tahanan effektif kira-kira 400 – 600 Ω .
5-7-3-2 Rangkaian Transmisi Ada 4 sistem rangkaian transmisi PLC, yaitu seperti tertera pada Gambar 5-86. Untuk ke-empat sistem ini karakteristik transmisinya berbeda. Impedansi frekuensi tinggi dari saluran transmisi berubah menurut komposisi rangkaian dan konstruksi salurannya. Namun harga-harga berikut ini dapat dipakai sebagai patokan:
Untuk pengaitan fasa-tanah Z = 400 Ω antar-fasa Z = 600 Ω
Attenuasi frekuensi tinggi dari saluran transmisi L. dinyatakan oleh rumus beri kut :
Gambar 5-85. Peralatan Pengait (Coupling Equipment) dalam Gardu. A: Jebakan Saluran (Line Trap) B: Kapasitor Pengait (Coupling Capacitor) C: Penyaring Pengait (Coupling Filter)
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
278
LO = α lL + 2Lc + La (dB) dimana: αo = konstanta attenuasi untuk pengaitan antar-fasa (dB/km);
berubah menurut konstruksi saluran transmisi; contoh untuk saluran yang umum tertera pada Gambar 6-90.
IL = panjang saluran transmisi (km) LC = atenuasi peralatan pengait per gardu (dB); biasanya diambil
2,5 dB (t4rmasuk rugi dijebakan saluran) (b) Pengaitan Dua-Fasa-Ke-Tanah (d) Pengaitan Antar-Rangkaian
Keterangan: LT ... Jebakan Saluran (Line Trap) CC ... Kapasitor Pengait Coupling Capacitor) TR ... Peralatan Pembawa (PLC)
La = rugi tambahan dalam hal pengaitan fasa-tanah biasanya diambil 5 dB.
5-7-3-2 Peralatan PLC
Peralatan PLC yang dipakai biasanya adalah jenis satu-saluran dan jenis tiga saluran (3-channel). Contoh spesifikasinya dapat dilihat pada Tabel 5-5.
Gambar 5-86. Sistem Rangkaian Transmisi dengan Pembawa (PLC)
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
279
Tabel 5-5 ada di lampiran (khusus tabel landscape)
di halaman 281
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
280
Tabel 5-6 lihat lampiran khusus tabel landscape
di halaman 282
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
281
5-7-4 Komunikasi Radio Telekomunikasi dengan pesawat radio banyak juga dipakai dalam industri tenaga listrik seperti terlihat pada Tabel 6-5. Penggunaannya kelihatannya tetap akan memegang peranan penting, terutama karena keunggulannya dalam keadaan bencana alam (angin topan, banjir) dibandingkan dengan komunikasi melalui kawat. Specifikasinya berubah dengan frekuensi kerja yang digunakan, yaitu frekuensi tinggi sekali (VHF) ke atas. Contoh spesifikasi peralatan komunikasi radio tertera pada Tabel 5-6.
Gambar 5-87. Contoh Peralatan Radio
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
282
5-7-4-1 Komunikasi VBF Frekuensi yang paling sering dipakai adalah antara 40 - 70 MHz dan
150 - 160 Hz. Pancaran gelombang radio VHF (30 - 300 MHZ) merupakan pancaran dengan gelombang langsung (direct wave), gelombang pantulan (reflected wave) dalarn jarak yang masih dapat dilihat (within line-of-sight distance), dan gclombang lenturan (diffracted wave) di luar jarak yang dapat dilihat (beyond line-of-sight distance). Karena jarang ada pancaran ionosfir untuk gelombang pendek, maka komunikasi ini tidak dapat dipakai untuk jarak jauh. Namun, sering kekuatan medan gelombang lenturan besar sekali, misalnya bila jalan pancaran itu dipotong oleh gunung yang terjal. Dalarn hal demikian, komunikasinya dimungkinkan untuk jarak jauh, yaitu kira-kira 100 km di luar jarak yang dapat di lihat.
Komunikasi radio VHF dari stasion ke stasion digunakan untuk kepentingan lokal dengan 1- 6 saluran (CH). Contoh pemancar, penerima dan antena radio terlihat pada Gambar 6-90 dan Gambar 6-91. Telekomunikasi radio mobil VHF sangat penting artinya bagi perusahaan listrik terutama dalam pemeliharaan saluran distribusi. Untuk pekerjaan tadi ada tiga jenis stasion. Yang pertama adalah stasion jinjingan (portable station) yang dapat dibawa oleh seorang pekerja, yang kedua yang dipasang dalam kendaraan (mobile station) dan yang ketiga adalah stasion pangkalan (base) yang dipakai di kantor (gardu) seksi pemeliharaan guna komunikasi dengan stasion jinjingan dan stasion mobil tadi. Sistem komunikasinya biasanya simplek (simplex, atau press-to-talk), dimana pembicaraan dilakukan bergantian.
Kadang-kadang stasion pangkalan dipasang di tempat yang paling tinggi (tidak di kantor seksi) untuk memungkinkan komunikasi dengan jarak pancaran yang lebih jauh. Station pangkalan di tempat yang tertinggi ini biasanya tidak berawak. Contoh komunikasi radio untuk pemeliharaan tertera pada Gambar 5-92.
5-7-4-2 Komunikasi Gelombang Mikro Jangkau frekuensi untuk komunikasi dengan gelombang mikro
(microwave) adalah 300 - 3000 MHz (dinamakan ultra-high frequency, disingkat UHF) dan 3000 30000 MHz (dinamakan super-high frequency, disingkat SHF)." Frekuensi UHF ke atas dinamakan gelombang mikro, meskipun ada juga yang menggunakan batas 1000 MHz. Frekuensi yang biasanya digunakan oleh perusahaan listrik'adalah frekuensi sekitar (band) 400 MHz, 2000 MHz dan 7000 MHz. Spesifikasi peralatan yang digunakan untuk komunikasi radio pada frekuensi sekitar 400 MHz terlihat pada Tabel 6-6. Pancaran gelombangnya terbatas pada jarak yang dapat dilihat, yaitu untuk komunikasi antara stasion dengan rangkaian komunikasi multiplek di bawah 24 saluran (CH). Akhir-akhir ini, sistem ini banyak dipakai guna komunikasi radio mobil untuk pemeliharaan saluran tenaga di sekitar kota (suburb). Cara kerjanya sama dengan komunikasi VHF.
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
283
Telekomunikasi dengan gelombang mikro digunakan untuk
saluran-saluran komunikasi yang terpenting yang memerlukan saluran bicara banyak. Dalam hal demikian, biaya pernbangilhan untuk setiap saluran bicara paling murah dibandingkandengan metoda komunikasi yang lain. Keuntungan yang lain adalah bahwa berisiknya sedikit, mutu suaranya baik dan keandalannya tinggi.
Dibandingkan dengan komunikasi PLC, komunikasi gelombang mikro lebih murah, karena harga kapasitor pengait dan jebakan saluran pada komunikasi PLC mahal. Kecuali itu, untuk PLC dibutuhkan peralatan yang penguatannya besar karena besarnya tegangan berisik korona terutama pada tegangan tinggi sekali. Oleh karena itu, bila saluran bicaranya enarn atau lebih, komunikasi gelombang mikro lebih ekonomis dan lebih stabil.
Gelombang mikro dipancarkan menurut garis lurus (seperti cahaya). Oleh karena itu pancaran gelombang mikro terbatas pada pancaran gelombang langsung dalam batas jarak yang dapat dilihat (kecuali pancaran gelombang terpencar di troposfir). Ini berarti, bahwa rugi pancaran (propagation loss) antara titik pancaran dan titik penerima berubah-ubah tergantung dari refraksi di udara (yang merupakan fungsi dari suhu di tanah, tekanan udara, kelembaban, kedudukan geografis) serta pengaruh gelombang pantulan (reflected). Fluktuasi ini dinamakan gejala menghilang (fading). Makin jauh jarak pancaran gelombang radio dan makin tinggi frekuensinya, makin besar gejala menghilangnya.
Kantor Dinas Pemeliharaan Saluran Transmisi
Gambar 5-88. Contoh Sistem Komunikasi Radio Mobil untuk Pemeliharaan Sa]uran.
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
284
Di angkasa bebas (free space) dimana pengaruh apapun terhadap pancaran gelombang tidak ada, nilai rata-rata dari rugi pancaran radio antara dua titik dinyatakan oleh rumus :
Γ = 10 log 10 (4πd/λ)2 (dB)
dimana Γ = rugi pancaran angkasa bebas (dB) λ = panjang gelombang (m) d = jarak antara titik pancaran dan titik penerima (m)
Dalam pernbangunan rangkaian gelombang mikro, stasion radionya harus diletakkan di tempat dimana gejala menghilang tidak akan banyak terjadi. Rangkaian itu juga harus direncanakan dengan memperhitungkan terjadinya rugi-pancaran karena gejala menghilang tadi.
Sebagai antena gelombang mikro digunakan lensa elektro-magnetik, antena reflektor tanduk atau antena parabolis. Karena pertimbangan ekonomis antena yang terakhir banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan listrik. Setiap antena ini dapat disesuaikan (matched) dengan kearahan (directivity) yang teliti dan perolehan daya (power gain) yang tinggi. Ciri telekomunikasi gelombang mikro dimungkinkan oleh mutu antena ini. Seperti terlihat pada Gambar 6-91 antena parabolis (parabolic antenna) terdiri dari reflektor parabolis dan radiator primer yang meradiasikan gelombang-gelombang ke reflektor. Gelombang-gelombang radio yang direfleksikan kemudian dipancarkan ke depan dengan arah yang tepat. Perolehan di depan antena dinyatakan oleh persarnaan:
G = 10 log10 (πD/λ)2gp (dB)
dimana G = perolehan (gain) mutlak (dB) D = garis tengah permukaan (celah) antena (m); biasanya 2-3 m λ = panjang gelombang (m) gp = koeffisien perolehan (biasanya 0,5 - 0,65)
Sebagai saluran penghubung (feeder line) biasanya dipakai kabel koaksial untuk frekuensi sekitar 2000 MHz, sedang penuntun-gelombang (wave guide) persegi, eliptis atau bulat dipakai untuk frekuensi sekitar 7000 MHz. Seperti terlihat pada Gambar 5-93 untuk memungkinkan pemantulan gelombang menurut arah tertentu digunakan reflektor logam datar yang dinamakan reflektor pasip. Reflektor ini biasanya berukuran 3 m x 4 m, 4 m x 6 m atau 6 m x 8 m. Contoh pemasangan terlihat pada Gambar 5-94.
Peralatan telekomunikasi gelombang mikro terdiri dari pesawat pemancar dan penerima radio, pesawat pengulang (repeater) dan alat frekuensi-pembawa. Dewasa ini semua peralatan ini sudah ditransistorkan. Contoh pesawat pengulang keadaan padat (solid state) terlihat pada Gambar 5-90. Pesawat pengulang biasanya menggunakan sistem rele detektip (detective relay system) yang menerima gelornbang mikro, mendemodulasikannya, mengambil bagian videonya, lalu memancarkannya kembali sesudah memodulasikannya lagi. Ada juga sistem heterodin, yang menguatkan gelombang mikro yang diterima sesudah mengubah
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
285
frekuensinya menjadi VHF, lalu memancarkannya kembali sesudah merubah frekuensinya menjadi gelombang mikro. Sistem terakhir ini jarang dipakai oleh perusahaan-perusahaan listrik. 5-8 Baterai dan Pengisinya 5-8-1 Baterai Ada dua macam sumber tenaga untuk kontrol di dalam G.I, ialah sumber arus searah dan sumber arus bolak-balik. Sumber tenaga untuk kontrol selalu harus mempunyai keandalan dan stabilitas yang tinggi. Karena persyaratan inilah dipakai baterai sebagai sumber arus searah. Ada dua macarn baterai (battery): timah hitam dan alkali. Sekarang baterai timah hitamlah yang banyak dipakai. Baterai alkali mempunyai keuntungan-keuntungan, misalnya, karena membutuhkan ruang yang lebih kecil, perubahan kapasitas akibat arus pelepasan, lebih kecil, arus sesaat dapat tinggi dan pemeliharaannya mudah. Tetapi baterai macam ini jarang dipakai karena harganya mahal dan umurnya sukar diperkirakan. Di Jepang standar" tegangan searah di terminal baterai adalah 110 V, dan di alat yang dikontrol 100 V. Jumlah baterai ditentukan dengan menganggap tegangan setiap selnya 2,15 V untuk baterai timah hitam dan 1,35 - 1,45 V untuk baterai alkali. Untuk baterai timah hitarn pada umumnya dipakai 52 sampai 55 sel. Kapasitas baterai ditentukan dengan memperhitungkan semua faktor yang menyangkut penurunannya selama dipakai, perubahannya oleh perubahan suhu dan jatuh tegangan, keperluan kapasitas yang diperlukan dengan memperkirakan beban terus menerus dan beban terputus-putus
Gambar 5-89. Lintasan Gelombang Mikro yang dipantulkan oleh reflektor Pasif.
Gambar 5-90. Reflektor Pasif (A) dan Antena Parabola (B) Gelombang Mikro (Panah menunjukkan Lintasan Gelombang
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
286
(continuous and intermittent load) yang harus dilayani selama terputusnya pelayanan normal, serta lamanya pemutusan pelayanan (biasanya 1 - 3 jam). Kapasitas yang diperlukan dalam keadaan terapung (floating) dihitung dengan cara berikut. Keadaan terapung adalah bila pada terminal baterai diterapkan tegangan pengisi yang konstan terus-menerus. Kapasitas C1 (Ampere-jam) untuk arus pelepasan maksimum sesaat i1(A), dan kapasitas C2 (Ampere-jam) untuk arus beban terus menerus i2 (A) pada saat pemutusan pelayanan untuk t2 (detik) dan arus beban terputus-putus i3 (A) pada saat pemutusan pelayanan untuk t3 (detik) dihitung.
Kemudian dipilih harga yang terbesar (periksa Gambar 6-95.(a)). Kapasitas C1 adalah:
C1 = 2/3 (i1 + i2) (Ampere-jam)
Kapasitas C2 dihitung dengan memisalkan bahwa kapasitas yang diperlukan adalah Cα (Ampere-jam) dan kapasitas sisa (residual) setelah pelepasan tahap pertama dan tahap kedua berturut-turut adalah Cα’, dan Cα”
Cα’ = Cα – (t2 – t3)i2/k2 Cα” = Cα’ - (i2 – i3)i3/k3
di mana k2 dan k3 adalah koefisien kapasitas untuk Cα/ i2, Cα’/(i2 – i3) yang dapat diperoleh dari Gambar 5-95 (b). Maka prosentase sisa adalah Cα” x 100 = α (%)
Cα Dengan cara yang sama dapat diperoleh dan β (%) dan γ % dengan memisalkan Cβ (Ampere-jam) dan Cγ (Ampere-jam). Dengan menggambar setiap prosentase kapasitas sisanya dapat ditarik garis lengkung seperti Gambar 6-95(c). Titik di mana prosentase sisanya 0 itulah C2,
Bila pengisian dan pelepasannya secara periodik maka C1 dan 3C2 dibandingkan; yang lebih besar itulah yang dipilih sebagai kapasitas yang diperlukan.
Kapasitas dasar (rated capacity) ditentukan dari harga kapasitas yang diperoleh di atas dengan memperhatikan penurunan kapasitas
selama dipakai (biasanya 80%), perubahan kapasitas akibat perubahan suhu
Ct = C25/1 + 0,008(t - 25) di mana C25 = kapasitas (Ampere-jam) pada suhu standard Ct = kapasitas (Ampere-jam) pada suhu tOC
T = suhu rata-rata (OC dari elektrolit pada 2 jam terakhir pelepasan.
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
287
Gambar 5-91. Penghitungan Kapasitas Baterai
Gambar 5-92. Lengkung Pelepasan Baterai
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
288
serta jatuh tegangan pada arus pelepasan maksimum sesaat (periksa Gambar 5-92).
5-8-2 Pengisi Sebagai pengisi (charger) dapat digunakan penyearah air raksa,
penyearah silikon, dan sebagainya; namun karena pertimbangan effisiensi, pemeliharaan dan karakteristiknya, yang banyak dipakai sekarang adalah penyearah selenium. Sistem pengisiannya ada 2 macam, sistem pengisian terapung (floating) dan sistem pengisian periodik. Sistem yang pertama adalah yang banyak dipakai karena umur baterai lebih lama, kapasitasnya dapat dipergunakan sepenuhnya serta perubahan tegangannya kecil. Arus output dari pengisi biasanya dibuat sekitar 1,25 kali arus dasar 10 jam dari baterainya. Namun dalam hal arus beban terus-menerus lebih besar dari arus dasar 10 jam dari baterai itu, arus output pengisi adalah arus beban terus-menerus ditambah dengan ½ arus dasar 10 jam dari baterai.
Saklar dan Pengaman
289
BAB VI SAKELAR DAN PENGAMAN PADA JARING DISTRIBUSI
6-1 Perlengkapan Penghubung dan Pemisah
Perlengkapan Hubung Bagi (PHB) dan Kendali ialah suatu perlengkapan atau peralatan listrik yang berfungsi sebagai pengendali, pengubung dan pelindung serta membagi tenaga listrik dari sumber tenaga listrik seperti; pembangkit, gardu induk, gardu distribusi dan transformator ke saluran pelayanan atau ke pelanggan. Jika komponen-komponen dari PHB terlihat dari luar tanpa perlindungan selungkup tertutup maka PHB itu dari jenis terbuka. Pembuatan lain adalah PHB tertutup. Menurut ukuran dan bentuknya PHB disebut elmari, kotak atau meja hubung bagi.
Ciri-ciri lemari hubung bagi antara lain: Selungkup dan kerangka pada umumnya terbuat dari besi Dapat bediri sendiri pada lantai, pada dinding atau dipasang dalam
dinding Di bagian papan terdapat panel atau konstruksi panel-panel logam
sebagai penutup dan perlindungan dari komponen-komponen yang terdapat di dalamnya dan panel itu ditempatkan alat pelayanan atau alat ukur.
Fungsi PHB untuk : o Mengendalikan sirkuit dilakukan oleh saklar utama o Melindungi sirkuit dilakukan oleh fase/pelebur o Membagi sirkuit dilakuan oleh pembagian jurusan/kelompok
Syarat-syarat umum : Secara umum sebuah PHB harus disusun dan dipasang sedemikian
rupa sehingga terlihat rapi dan teratur, selain itu keberadaan PHB juga menentukan bahwa pemeliharaan, pemeriksaan dan pelayanan harus dapat dilaksanakan dengan mudah dan aman. Selanjutnya sesuai dengan syarat pengoperasian kemudahan pengamatan pengukuran, penekanan tombol, pemutaran atau pelayanan saklar, maka perkerjaan-pekerjaan ini harus dapat dilakukan dari bagian depan, tanpa alat bantuan, seperti tangga atau alat-alat lainnya.
Sehubungan dengan itu syarat PHB juga menentukan bahwa di bagian depan, lorong dan sisi kiri kanan PHB harus terdapat ruang bebas selebar sekurang-kurangnya 0,75 meter untuk tegangan rendah atau 1 meter pada tegangan menengah dan tinggi PHB sekurang-kurangnya
Saklar dan Pengaman
290
2 meter. Lorong yang di sisi kanan kirinya terdapat instalasi listrik tanpa dinsing pengaman, lebarnya harus sekurang-kurangnya 1,5 meter.
Di sekitar PHB tidak boleh diletakkan barang yang mengganggu kebebasan bergerak. Untuk pemasangan pada dinding di tempat-tempat umum lemari dan kotak PHB harus dipasang pada ketinggian sekurang-kurangnya 1,2 meter dari lantai. Pada instalasi perumahan ketinggian ini ditetapkan 1,5 meter dari lantai.
Syarat PHB menetapkan bahwa lemari dan kontak hubung bagi tidak boleh dipasang di kamar mandi, tempat cuci tangan, di atas kompor atau di atas bak air.
6-1-1 Macam-macam PHB : Menurut kebutuhannya PHB dibedakan menjadi 2 macam yaitu : PHB
Utama dan PHB sub instalasi atau PHB cabang.
• PHB Utama ialah PHB yang menerima aliran tenaga listrik dari sumber melalui saklar utama konsumen dan membagikan tenaga listrik tersebut ke seluruh alat pemakai pada instalasi konsumen.
• PHB Sub Instalasi atau PHB Cabang ialah PHB dari suatu instalasi untuk mensuplai tenaga listrik kepada satu konsumen dan instalasi tersebut merupakan bagian dari instalasi yang mensuplai konsumen tunggal atau lebih.
Menurut tegangan sumbernya, PHB dibedakan menjadi sesuai dengan tingkat tegangan sistemnya yaitu : PHB tegangan rendah (TR), PHB tegangan menengah (TM) dan PHB tegangan tinggi (TT).
• PHB TR yaitu PHB yang banyak dipasang pada instalasi baik milik PLN maupun milik pelanggan, PHB yang terpasang milik pelanggan, PHB yang terpasang milik PLN biasanya ditempatkan gardu induk distribusi sisi sekunder trafo distribusi sedangkan PHB yang di pelanggan biasanya terpasang pada dinding atau ruangan tertentu setelah APP ditempat pelanggan tersebut.
• PHB TM ialah PHB yang terdapat pada pembangkit atau GI sisi TM berbentuk lemari panel (kubikel) tertutup terbuat dari bahan besi atau berbentuk gardu sel terbuka yang dilengkapi peralatan ukur dan pengaman (proteksi).
• PHB TT adalah PHB yang menggunakan peralatan-peralatan dengan kapasitas yang besar dan mempunyai resiko bahaya yang tinggi pula sehingga pemasangan PHB TT ini biasanya ditempat khusus dan terbuka (switch yard) yang dilengkapi rambu-rambu, pagar dan peralatan pengaman yang memadai.
Menurut tipenya PHB di kelompokkan menjadi 2 tipe yaitu tipe tertutup dan tipe terbuka.
Saklar dan Pengaman
291
• PHB dengan tipe tertutup yaitu apabila seluruh komponen PHB berada disuatu tempat yang tertutup oleh selungkup/pelindung mekanis maupun pelindung elektris.
• PHB tipe terbuka yaitu PHB yang semua peralatan atau komponennya berada diluar dan tampak secara kasar mata dan dilengkapi dengan pagar maupun peralatan isolasi huna melindungi dari bahaya mekanis dan elektrisnya.
6-1-2 Bentuk PHB 1. Bentuk Tertutup
2. Bentuk Terbuka
6-1-3 Busbar 1. Tipe Tertutup (Close Type) Tipe tertutup ini banyak digunakan dan dikembangkan saat ini di pembangkitan atau digardu induk yang areal kerjanya tidak luas, biasanya dipasang di lemari hubung bagi atau kubikel karena bentuknya yang sederhana dengan konstruksi pemasangan yang sederhana dengan konstruksi pemasangan yang praktis dan lebih aman, sebab setiap pintu
Gambar 6-1. Bentuk lemari dengan bagian yang dapat ditarik keluar
Gambar 6-2. Busbar tipe terbuka (pandangan depan)
Saklar dan Pengaman
292
lemari PHB nya dilengkapi dengan penataan sistem interlock dimana saklar pentanahannya terdapat didalam PHB tersebut.
Apabila pintu PHB akan dibuka maka terlebih dahulu posisi PMT harus terbuka dan saklar pentanahan dimasukkan, baru pintu PHB dapat dibuka. Begitu pula pada waktu akan menutup PMT maka posisi pintu tertutup dan saklar pentanahannya dalam keadaan terbuka.
2. Tipe Terbuka (Open Type) Busbar pada tipe terbuka ini banyak dijumpai digardu sel atau gardu open type, dimana semua peralatan termasuk rel pengumpul (Busbar) kelihatan secara visual. Hal ini menunjukkan bahwa semua peralatan yang terpasang memerlukan tempat tersendiri sehingga membutuhkan areal yang luas untuk tipe terbuka ini, karena masing-masing peralatan secara utuh akan terpasang pada PHB tipe terbuka ini.
Oleh karena keadaan terbuka tersebut sehingga bagian-bagian yang bertegangan dari PHB ini sangat membahayakan operatornya, untuk mengatasi hal tersebut maka pada PHB/Gardu terbuka selalu diberi pagar dan tanda rambu keselamatan kerja untuk membatasi daerah berbahaya dan memperingatkan kepada semua petugas agar lebih berhati-hati.
6-1-4 Perlengkapan Hubung Bagi Tegangan Rendah (PHB TR) Yang dimaksud dengan PHB TR adalah Perlengkapan Hubung Bagi
yang dipasang pada sisi TR atau sisi sekunder Trafo sebuah gardu Distribusi baik Gardu beton, Gardu kios, Gardu portal maupun Gardu cantol. Adapun PHB TR yang banyak kita jumpai adalah PHB TR yang ada pada Gardu Trafo Tiang (GTT).
PHB TR yang terpasang pada Gardu Trafo Tiang berbentuk lemari besi yang didalamnya terdapat komponen-komponen antara lain :
1. Kerangka / Rak TR 2. Saklar Utama 3. NH Fuse Utama
Gambar 6-3. Salah satu contoh Busbar tipe tertutup (Kubikel)
Saklar dan Pengaman
293
Gambar 6-5. PHB TR (Out Door)
Gambar 6-4. PHB/Gardu terbuka
Pintu kawat raam
CB CT PT
UNP. 10
APP
Saklar dan Pengaman
294
4. Rel Tembaga 5. NH Fuse jurusan 6. Isolator penumpu Rel 7. Sirkuit Pengukuran 8. Alat ukur Ampere & Volt meter 9. Trafo Arus (CT)
10. Sistem Pembumian 11. Lampu Kontrol / Indikator
6-1-5 Fungsi PHB TR Fungsi atau kegunaan PHB TR adalah sebagai penghubung dan
pembagi atau pendistribusian tenaga listrik dari out put trafo sisi tegangan rendah TR ke Rel pembagi dan diteruskan ke Jaringan Tegangan Rendah (JTR) melalui kabel jurusan (Opstyg Cable) yang diamankan oleh NH Fuse jurusan masing-masing.
Untuk kepentingan efisiensi dan penekanan susut jaringan (loses) saat ini banyak unit PLN yang mengambil kebijaksanaan untuk melepas atau tidak memfungsikan rangkaian pengukuran maupun rangkaian kontrolnya, hal ini dimaksudkan agar tidak banyak energi listrik yang
Gambar 6-6. Rangkaian Utama, Pengukuran & Kontrol PHB TR.
Keterangan Gambar: 1. Saklar Utama 2. NH Fuse Jurusan 3. Volt Meter 4. Fuse Kontrol 5. Kabel Juruan
Saklar dan Pengaman
295
mengalir ke alat ukur maupun kontrol terbuang untuk keperluan kontrol dan pengukuran secara terus menerus, sedangkan untuk mengetahui besarnya beban maupun tegangan, dilakukan pengukuran pada saat di perlukan saja dan bisa menggunakan peralatan ukur portable seperti AVO atau Tang Ampere saja.
6-1-6 Konstruksi PHB TR Menurut Konstruksinya PHB TR dibagi menjadi 2 (dua) macam
konstruksi yaitu : 1. Konstruksi PHB TR 2 Jurusan 2. Konstruksi PHB TR 4 Jurusan
6-1-7 Pengoperasian PHB TR
Untuk mengoperasikan PHB TR baru harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh manajemen dalam hal ini adalah unit operasi Jaringan Tegangan Rendah (JTR) dalam bentuk Standing Operation Procedure (SOP).
Adapun pembuatan SOP bisa mengambil contoh dari beberapa referensi antara lain:
Instruction Manual Books
Gambar 6-7. PHB-TR Dua Jurusan dan Empat Jurusan
Saklar dan Pengaman
296
Data Spesifikasi peralatan PHB TR Operation Guidance Kondisi Jaringan Pengalaman (Experience) Dan lain-lain
6-1-8 Konstruksi PHB TR Berdiri (Standing)
Keterangan Gambar: 1. Saklar Utama 2. NH Tuse Juruan 3. Volt meter 4. Fuse Kontrol 5. Kabel Jurusan
Gambar 6-8. Konstruksi PHB-TR type berdiri (Standing)
Saklar dan Pengaman
297
Langkah-langkah Kerja Pengoperasian PHB-TR
1. Petugas Pelaksana Menerima PK dari Asman Distrbusi untuk melakukan pengoperasian Peralatan Hubung Bagi Tegangan Rendah (PHB – TR) baru.
2. Siapkan Alat Kerja, Alat Ukur, Alat K-3. Material Kerja dan Alat Bantu sesuai dengan kebutuhan
3. Setelah Petugas sampai di Lokasi gunakan Alat K-3 dan selanjutnya lapor ke Posko, petugas akan mengoperasikan PHB - TR baru
4. Periksa konstruksi PHB – TR baru meliputi : - Buka tutup Saklar Utama - Lampu kerja dan Lampu Test - Isolator Fuse Holder - Konduktor pentanahan (arde) - Kekencangan Baut - Rating NH Fuse sesuai dengan kapasitas Trafo Terpasang
5. Barikan Vaselin pada Pisau Saklar Utama dan Fuse Holder
6. Lakukan pengukuran tahanan isolasi antar arel dan antara Rel dengan Body serta tahanan pembumian dan dicatat dalam Formulir Berita Acara (BA).
Gambar 6-9. Diagram Pengawatan PHB-TR
Kondisi (Isi) Panel
Saklar dan Pengaman
298
7. Bersihkan Rel. Dudukan Fuse Holder, Pisau Saklar Utama (Hefboom Saklar). Sepatu Kabel dari kotoran/korosi. Dan bersihkan ruangan dalam panel hubung bagi.
8. Periksa kekencangan peningkatan mur/baut pada Saklar Utama Sepatu Kabel, Rel, Fuse Holder, kondisi isolator binnen dan Sistem pembumian.
9. Lakukan pemeriksaan hasil pekerjaan secara visual dan amankan seluruh peralatan kerja.
10. Lapor ke posko bahwa kondisi PHB – TR dan Petugas dalam keadaan aman dan selanjutnya meminta tegangan dimasukkan (pemasukan CO gardu dilaksanakan oleh petugas operasi SUTM).
11. Setelah menerima ijin pemasukan tegangan dari posko masukan CUT OUT (CO).
12. Lakukan penukaran tegangan pada sisi masuk saklar utama dan amati putaran fasa dan selanjutnya catat dalam formulir BA.
13. Masukkan saklar utama (Hefbom Saklar).
14. Masukkan NH Fuse masing-masing jurusan.
15. Lapor ke posko, bahwa pekerjaan pengoperasian PHB – TR baru telah selesai dan petugas akan meninggalkan lokasi pekerjaan.
16. Lepaskan Alat K-3 yang sudah tidak dipergunakan lagi.
17. Buat laporan dan berita acara pelaksanaan pekerjaan pengoperasian PHB – TR baru.
18. Buat laporan pekerjaan pengoperasian PHB – TR baru dan berita acara diserahkan kepada Asman Distribusi.
6-1-9 Pemeliharaan PHB TR Sebagaimana pengoperasian PHB TR pada kegiatan pemeliharaanpun
diperlukan langkah-langka atau prosedur pemeliharaan rutin periodik dan berkala yang disahkan oleh manajemen unit setempat sebagai prosedur tetap dalam bentuk SOP.
Langkah-langkah pemeliharaan antara lain : Persiapan Pemeliharaan Pemeriksaan dan Pengukuran Pemeriksaaan Pemeliharaan Pemeriksaan Hasil Pemeliharaan Pembuatan Laporan Pemeliharaan
Pelaksanaan Pemeliharaan PHB TR Di bawah ini ditunjukkan gambar pelaksanaan Pemeliharaan PHB
TR dengan membongkar, membersihkan, memeriksa, mengganti dengan peralatan yang baru bila peralatan yang diperiksa tersebut sudah rusak dan
Saklar dan Pengaman
299
memasangkan kembali ke posisi semula kemudian mencoba dioperasikan oleh teknisi pemeliharaan yang selanjutnya dibuatkan laporan pengganti peralatan hasil pemeliharaan PHB TR tersebut.
Langkah-langkah Kerja Pelaksanaan Pemeliharaan PHB-TR 1. Petugas Pelaksana Menerima PK dari Asman Distrbusi untuk
melakukan pemeliharaan Peralatan Hubung Bagi Tegangan Rendah (PHB – TR) baru.
2. Siapkan Alat Kerja, Alat Ukur, Alat K-3. Material Kerja dan Alat Bantu sesuai dengan kebutuhan
3. Setelah Petugas sampai di Lokasi gunakan Alat K-3 dan selanjutnya lakukan pengukuran tegangan, arus beban, dan putaran fasa serta catat dalam formulir.
4. Lepas beban jurusan dan buka saklar utama.
5. Laporkan pada Posko bahwa pekerjaan akan dilaksanakan dan meminta pelepasan CO gardu (pelepasan CO gardu dilaksanakan oleh petugas operasi SUTM).
6. Tanahkan (Grounding) seluruh kabel jurusan dengan menggunakan Grounding cabel TR,
7. Bersihkan Rel, Dudukan Fuse Holder, Pisau Saklar Utama (Hefboom Saklar). Sepatu Kabel dari kotoran/korosi. Dan bersihkan ruangan dalam Panel Hubung Bagi.
Gambar 6-10. Pemeriksaan titik sambungan dengan Thermavision
Saklar dan Pengaman
300
Gambar 6-11. Pelaksanaan Pemeliharaan Salah Satu Komponen PHB TR
Gambar 6-12. Diagram Segaris Gardu Trafo Tiang (GTT)
Saklar dan Pengaman
302
Gambar 6-14. Diagram Satu Garis PHB-TR Gardu Tiang Trafo
Gambar 6-15. Pemasangan PHB-TR pada Gardu Control
Saklar dan Pengaman
303
8. Periksa kekencangan peningkatan mur/baut pada Saklar Utama Sepatu, Kabel, Rel, Fuse Holder, Kondisi Isolator Binnen dan Sistem Pembumian.
9. Bila ada komponen PHB-TR yang rusak maka perbaiki atau ganti baru.
10. Berikan Vaseline pada Pisau Saklar Utama, Terminal Fuse Holder.
11. Ukur dan Catat nilai tahanan isolasi antar Rel dan atau Rel terhadap body setelah Tahanan Pentanahan dan catat dalam formulir berita acara (BA).
12. Lakukan pada posko bahwa pekerjaan pemeliharaan telah selesai dan meminta pemasukan CO gardu (pemasukan CO gardu dilaksanakan oleh petugas operasi SUTM).
13. Lepaskan pentanahan (Grounding cable TR) pada seluruh kabel jurusan.
14. Laporkan pada posko bahwa pekerjaan pemeliharaan telah selesai dan meminta pemasukan CO gardu (pemasukan CO gardu dilaksanakan oleh petugas operasi SUTM).
15. Masukkan saklar utama tanpa beban, kemudian ukur besaran tegangan antara fasa dan fasa, dan atara fasa dengan nol di rel, serta check arah putaran fasa dan selanjutnya catat dalam formulir BA.
16. Lakukan pengecekkan Rating NH Fuse untuk disesuaikan dengan data Fuse semula.
17. Masukkan NH Fuse jurusan secara bertahap.
18. Lakukan pengukuran beban dan catat dalam formulir BA.
19. Tutup dan kunci pintu Panel PHB TR.
20. Tutup ke Posko bahwa pekerjaan memelihara PHB TR telah selesai dan petugas akan meninggalkan lokasi pekerjaan.
21. Lepaskan alat K-3 yang sudah tidak dipergunakan lagi.
22. Buat laporan Berita Acara pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan PHB TR.
23. Laporkan penyelesaian pekerjaan dan penyerahan Formulir BA kepada Asman Distribusi.
6-2 Transformator Transformator adalah peralatan pada tenaga listrik yang berfungsi
untuk memindahkan/menyalurkan tenaga listrik tegangan rendah ke tegangan menengah atau sebaliknya, sedangkan prinsip kerjanya melalui kopling magnit atau induksi magnit.
Saklar dan Pengaman
304
6-2-1 Bagian-Bagian Dari Transformator 6-2-1-1 Inti Besi
Inti besi tersebut berfungsi untuk membangkitkan fluksi yang timbul karena arus listrik dalam belitan atau kumparan trafo, sedang bahan ini terbuat dari lempengan-lempengan baja tipis, hal ini dimaksudkan untuk mengurangi panas yang diakibatkan oleh arus eddy (weddy current).
6-2-1-2 Kumparan Primer dan Kumparan Sekunder Kawat email yang berisolasi terbentuk kumparan serta terisolasi baik
antar kumparan maupun antara kumparan dan inti besi. Terdapat dua kumparan pada inti tersebut yaitu kumparan primair dan kumparan skunder, bila salah satu kumparan tersebut diberikan tegangan maka pada kumparan akan membangkitkan fluksi pada inti serta menginduksi kumparan lainnya sehingga pada kumparan sisi lain akan timbul tegangan.
6-2-1-3 Minyak Trafo Belitan primer dan sekunder pada inti besi pada trafo terendam
minyak trafo, hal ini dimaksudkan agar panas yang terjadi pada kedua kumparan dan inti trafo oleh minyak trafo dan selain itu minyak tersebut juga sebagai isolasi pada kumparan dan inti besi.
6-2-1-4 Isolator Bushing Pada ujung kedua kumparan trafo baik primair ataupun sekunder
keluar menjadi terminal melalui isolator yang juga sebagai penyekat antar kumparan dengan body badan trafo.
6-2-1-5 Tangki dan Konserfator Bagian-bagian trafo yang terendam minyak trafo berada dalam
tangki, sedangkan untuk pemuaian minyak tangki dilengkapi dengan konserfator yang berfungsi untuk menampung pemuaian minyak akibat perubahan temperature.
6-2-1-6 Katub Pembuangan dan Pengisian Katup pembuangan pada trafo berfungsi untuk menguras pada
penggantian minyak trafo, hal ini terdapat pada trafo diatas 100 kVA, sedangkan katup pengisian berfungsi untuk menambahkan atau mengambil sample minyak pada trafo.
6-2-1-7 Oil Level Fungsi dari oil level tersebut adalah untuk mengetahui minyak pada
tangki trafo, oil level inipun hanya terdapat pada trafo diatas 100 kVA.
6-2-1-8 Indikator Suhu Trafo Untuk mengetahui serta memantau keberadaan temperature pada oil
trafo saat beroperasi, untuk trafo yang berkapasitas besar indikator limit tersebut dihubungkan dengan rele temperature.
Saklar dan Pengaman
305
6-2-1-9 Pernapasan Trafo Karena naik turunnya beban trafo maupun suhu udara luar, maka
suhu minyaknya akan berubah-ubah mengikuti keadaan tersebut. Bila suhu minyak tinggi, minyak akan memuai dan mendesak udara diatas permukaan minyak keluar dari tangki, sebaliknya bila suhu turun, minyak akan menyusut maka udara luar akan masuk kedalam tangki.
Kedua proses tersebut diatas disebut pernapasan trafo, akibatnya permukaan minyak akan bersinggungan dengan udara luar, udara luar tersebut lembab. Oleh sebab itu pada ujung pernapasan diberikan alat dengan bahan yang mampu menyerap kelembaban udara luar yang disebut kristal zat Hygrokopis (Clilicagel).
6-2-1-10 Pendingin Trafo Perubahan temperature akibat perubahan beban maka seluruh
komponen trafo akan menjadi panas, guna mengurangi panas pada trafo dilakukan pendingin pada trafo, guna mengurangi pada trafo dilakukan pendinginan pada trafo. Sedangkan cara pendinginan trafo terdapat dua macam yaitu : alamiah/natural (Onan) dan paksa/tekanan (Onaf).
Pada pendinginan alamiah (natural) melalui sirip-sirip radiator yang bersirkulasi dengan udara luar dan untuk trafo yang besar minyak pada trafo disirkulasikan dengan pompa. Sedangkan pada pendinginan paksa pada sirip-sirip trafo terdapat fan yang bekerjanya sesuai setting temperaturnya.
6-2-1-11 Tap Canger Trafo (Perubahan Tap) Tap changer adalah alat perubah pembanding transformasi untuk
mendapatkan tegangan operasi sekunder yang sesuai dengan tegangan sekunder yang diinginkan dari tegangan primer yang berubah-ubah.
Tiap changer hanya dapat dioperasikan pada keadaan trafo tidak bertegangan atau disebut dengan “Off Load Tap Changer” serta dilakukan secara manual.
6-2-2 Impedansi Trafo Bila kumparan primer suatu transformator dihubungkan dengan
sumber tegangan V1 yang sinusoid, akan mengalirlah arus primer lg yang juga sinusoid dan dengan menganggap belitan N1 reaktif murni. lg akan
Gambar 6-16. Rangkaian Dasar Trafo
Saklar dan Pengaman
306
tertinggal 900 dari V1 (gambar 1b) Arus primer lg menimbulkan fluks ( ) yang sefasa dan juga berbentuk sinusoid.
= maks Sin wt (6-1)
Fluks yang sinusoid ini akan menghasilkan tegangan induksi e1 (Hukum Farraday).
(6-2)
(6-3)
Harga efektifnya
(6-4)
Pada rangkaian sekunder fluks ( ) bersama tadi menimbulkan
(6-5)
(6-6)
(6-7)
Sehingga
(6-8)
dtdNe 11
daritertinggalwtCoswN
dtwtSindNe maks
maks
01
90
(11
maksmaks fNfNE 1
11 44,4
22
dtdNe 22
tNe m cos22
maksfNE 22 44,4
2
1
2
1
NN
EE
Gambar 6-17. Diagram Arus Penguat
Saklar dan Pengaman
307
Dengan mengabaikan rugi tahanan dan adanya fluks bocor.
(6-9)
a = perbandingan transformator
Dalam hal ini tegangan induksi E1 mempunyai kebesaran yang sama tetapi berlawanan arah dengan tegangan sumber V1.
6-2-3 Arus Penguat Arus primer lo yang mengalir pada saat kumparan sekunder tidak
dibebani disebut arus penguat. Dalam kenyataannya arus primer lo bukanlah merupakan arus induktif murni, hingga ia terdiri atas dua komponen (gambar 1).
1. Komponen arus pemagnetan lM yang menghasilkan fluks ( ). Karena sifat besi yang nonlinier (ingat kurva B-H) maka arus pemagnetan lM dan juga fluks ( ) dalam kenyataan tidak berbentuk sinusoid (gambar 1).
2. Komponen arus rugi tembaga lc menyatakan daya yang hilang akibat adanya rugi histeresis dan arus eddy lc sefasa dengan V1 dengan demikian hasil perkaliannya (lc x V1) merupakan daya (watt) yang hilang.
6-2-4 Trafo dalam Keadaan Berbeban Apabila kumparan sekunder dihubungkan dengan ZL l2 mengalir pada
kumparan sekunder, dimana l2 = V2 / ZL dengan O2 = factor kerja beban.
Arus beban l2 ini akan menimbulkan gaya gerak magnet (ggm) N2 l2 yang cenderung menentang fluks ( ) bersama yang telah ada akibat arus pemagnetan lM. Agar fluks bersama itu tidak berubah nilainya pada kumparan primer oleh arus beban l2 hingga keseluruhan arus yang mengalir pada kumparan magnet primer menjadi :
l1 = lO + l2 (6-10)
aNN
VV
EE
2
1
2
1
2
1
E2 Z2 V2
I2 I1
V1 E1
Gambar 6-18. Rangkaian Trafo Berbeban
Saklar dan Pengaman
308
6-2-5 Pemeliharaan Gardu Trafo Tiang (GTT) Tenaga Listrik merupakan suatu kebutuhan pokok bagi masyarakat
saat ini, oleh karena itu Tenaga Listrik harus dapat tersedia secara terus-menerus dengan mutu dan keadaan yang tinggi, untuk dapat tercapainya hal tersebut salah satu usaha adalah dengan tetap terpeliharanya instalasi Sistem Tenaga Listrik di sisi Pembangkitan, Penyeluran dan Distribusinya.
Sebagaimana peralatan pada umumnya, peralatan yang operasi dalam instalasi Tenaga Listrik perlu dipelihara, hal ini bertujuan untuk mempertahankan unjuk kerja peralatan tersebut, terpeliharanya instalasi tenaga listrik dengan baik dapat mempertahan mutu dan kendala penyaluran tenaga listrik.
Gardu Trafo Tiang (GTT) adalah merupakan salah satu komponen instalasi tenaga listrik yang terpasang di Jaringan Distribusi berfungsi sebagai trafo daya penurun tegangan dari tegangan menengah ke tegangan rendah, dan selanjutnya tegangan rendah tersebut disalurkan ke konsumen. Mengingat fungsi dan harga dari trafo tersebut cukup mahal bila dibandingkan dengan peralatan distribusi lainnya, maka pemeliharaan preventif yang dilakukan secara intensif, dengan kriteria pemeliharaan yang jelas untuk setiap komponen GTT dan ditangani oleh tenaga yang terampil dengan peralatan yang memadai agar pemeliharaan tersebut berjalan dengan efektif.
6-2-5-1 Komponen Utama GTT Secara umum komponen utama GTT adalah sebagai berikut :
1. Transformator : berfungsi sebagai trafo daya merubah tegangan menengah (20 kV) menjadi tegangan rendah (380/200) Volt.
2. Fuse Cut Out (CO) : sebagai pengaman penyulang, bila terjadi gangguan di gardu (trafo) dan melokalisir gangguan di trafo agar peralatan tersebut tidak rusak. CO di pasang pada sisi tegangan menengah (20 kV).
3. Arrester : sebagai pengaman trafo terhadap tegangan lebih yang disebabkan oleh samabaran petir dan switching (SPLN se.002/PST/73).
4. NH Fuse : sebagai pengaman trafo terhadap arus lebih yang terpasang di sisi tegangan rendah (220 Volt), untuk melindungi trafo terhadap gangguan arus lebih yang disebabkan karena hubung singkat dijaringan tegangan rendah maupun karena beban lebih.
5. Grounding Arrester : untuk menyelurkan arus ketanah yang disebabkan oleh tegangan lebih karena sambaran petir dan switching.
6. Graunding Trafo : untuk menghindari terjadi tegangan lebih pada phasa yang sehat bila terjadi gangguan satu fasa ketanah mauoun yang disebutkan oleh beban tidak seimbang.
Saklar dan Pengaman
309
7. Grounding LV Panel : sebagai pengaman bila terjadi arus bocor yang mengalir di LV panel.
6-2-5-2 Peralatan Pendukung Alat Kerja
Agar pekerjaan dapat terlaksana dengan baik perlu didukung oleh peralatan yang memadai baik peralatan mekanik maupun elektrik. Adapun peralatan kerja yang dibutuhkan sebagai berikut :
Alat Ukur AVO Meter Megger 1.0 Volt, 5.000 Volt, 10.000 Volt Earth Tester Tang Amper dengan range 1.000 Amper Infrares Drivelt/Phasa Detector dll.
Peralatan Shcakel Stick 20kV 13 meter Kunci Shock (satu set) Kunci Ring (satu set) Kunci Inggris Tang Kombinasi Tang Kupas/Potong Obeng Minus Obeng Plus Gergaji Besi Palu Corong Minyak Slang Plastik Pompa Minyak (plastik) Kain Lap Majun Kertas Gosok Dies Compression Cable Cutter 600 – 900 mm Tangga Fiber Glass 7 m Stainless Steel Belt/Stopping Tool Boto Kosong Bersih + Tutup Kuas Kikir dll.
Perlengkapan K3 Sabuk Pengaman Helm P3K Sarung Tangan Katun Sepatu Kerja dan lain-lain
Saklar dan Pengaman
310
Material Pemeliharaan Daftar material untuk pekerjaan pemeliharaan seperti tercantum pada Tabel 6-1 berikut:
Tabel 6-1. Material Pemeliharaan GTT
No. Material Satuan Jumlah 1 Ground rod 2,5 m Buah 2 2 Ground rod 1,5 m Buah 4 3 Cincin rod Buah 6 4 NYA 50 mm2 Meter 10 5 NYA 70 / 95 mm2 Meter 6 6 NYA 120 / 150 mm2 Meter 6 7 BC Draad 50 mm Meter 5 8 AAAC 70 mm2 Meter 46 9 NYAF 50 mm Meter 2
10 CCT 6 T 6 (95 / 95 mm) Buah 6 11 STT 5 T 5 (70 / 70 mm) Buah 6 12 STT 7 T 7’ (120 / 120 mm) Buah 4 13 STT 8 T 8 (150 / 150 mm) Buah 4 14 SAA 5 T 5 (70 / 70 mm) Buah 7 15 SAA 5 T 4 (70 / 50 mm) Buah 6 16 SAT 4 (50 mm) Buah 6 17 SKT 6 (95 mm) Buah 12 18 SKT 7 (120 mm) Buah 12 19 SKT 8 (150 mm) Buah 8 20 SKA 5 (70 mm) Buah 2 21 CCO 5 T 5 (70 / 70 mm) Buah 7 22 Skaklar Utama 630 A (bila rusak) Buah 1 23 Fuse base 400 A Buah 6 24 Fuse Holder/Smeldraad Holder Buah 6 25 Smel Draad 80 – 200 A Buah 6 26 Fuse Ling 3 – 8 A Buah 3 27 Pipa PVC AW ¾” Buah 6 28 Stopping Buckle Buah 10 29 Link Buah 10 30 Isolasi PVC Pipa Rol 1 31 Isolator Scot 23 Rol 1 32 Contac Cliner/Sakapen Botol 1 33 Silikon gress/Vaseline CC 50 34 Stainless Steel Strap Meter 15 35 Semen Kg 4 36 Minyak Trafo Liter 25 37 Alkohol Liter 1 38 Kain Majun Kg 1 39 Cat/Meni Besi (abu-abu) Kg 1 40 Thinner Liter 1 41 Engsel Buah 1
Saklar dan Pengaman
311
6-2-5-3 Pelaksanaan Pemeliharaan Persiapan
Agar pekerjaan GTT dapat berjalan sesuai dengan rencana, maka perlu dilakukan persiapan sebelum pelaksanaan, persiapan tersebut menjadi :
1. Melakukan survai lapangan : survai bertujuan untuk melihat secara langsung keadaan GTT dengan mengadakan pemeriksaan secara Visual, Mekanik, Elektrical, Pengukuran (beban, tegangan) atau pengukuran suhu/sambungan/NH fuse dengan menggunakan Infra Red. Semua hasil pemeriksaan tersebut dicatat dan dievaluasi sebagai bahan masukkan untuk membuat rencana pemeliharaan terutama yang menyngkut kebutuhan material dan perkiraan waktu pemadaman.
2. Penyampaian rencana dan kondisi lapangan ke Pengawas Pelaksana Pekerjaan : hal ini untuk dapat memberikan gambaran pada pengawas pelaksana agar sebelum melaksanakan pekerjaan dapat mempersiapkan sesuatunya dengan baik dan membuat strategi pelasanaannya, dan dari informasi tersebut diharapkan dapat mengurangi kesulitan dalam pelaksanaan pekerjaan.
3. Pemberitahuan pemadaman ke konsumen : karena pelaksanaan pemeliharaan GTT diperlukan pembebasan tegangan, maka sebelum pelaksanaan pekerjaan, konsumen yang dipasok oleh GTT tersebut perlu diberi informasi tentang rencana pemadaman, informasi pemadaman tersebut dapat di informasikan melalui media massa (radio, koran), untuk pelanggan industri bila perlu diberi surat tersendiri. Untuk pelanggan 3 phasa perlu diingatkan agar memasang pengaman phasa under voltage, untuk mengamankan bila terjadi hilang tegangan 1 phasa.
6-2-5-4 Pelaksanaan Pekerjaan a. Material, Alat kerja dan SDM : material dan alat kerja harus betul-betul
dipersiapkan dengan baik, ketidak lengkapan material maupun alat kerja akan menyebabkan pekerjaan menjadi lama dan juga dapat menyebabkan hasil kerja tidak sempurna bahkan dapat juga menambah kerusakan pada komponen yang dikerjakan dengan menggunakan alat yang tidak seharusnya (contoh pengerasan mur/baut dengan menggunakan tang). Selain dari material dan alat kerja yang lebih penting adalah sumber daya manusia (SDM), material dan alat kerja lengkap tidak didukung dengan SDM yang memadai tidak ada artinya, oleh sebab itu para pelaksana perlu diberi Pedoman atau SOP yang dapat digunakan sebagai petunjuk pelaksanaan pekerjaan.
b. Pengukuran Parameter yang diperlukan : untuk mengetahui hasil kerja yang telah dilakukan, salah satunya adalah dengan membandingkan parameter sebelum dengan setelah pekerjaan dilaksanakan,
Saklar dan Pengaman
312
parameter yang perlu dilakukan pengukuranantara lain Tegangan, Arus, Temperatur, dan Tahanan pentanahan.
c. Pembebasan Tegangan : setelah dipastikan bahwa ijin pemadaman dan fisik lapangan sudah siap, kemudian dilakukan pembebasan beban pada GTT tersebut dan dilakukan dan dilanjutkan dengan saklar utama (helboom), bila tidak terpasang helboom dapat melepas NH fuse jurusan di mulai dari phasa s, r, t, untuk menghindari ketidak imbangan pada konsumen 3 phasa sekaligus, sedangkan untuk pembebasan tegangan dilakukan dengan melepas Fuse Cut Out (CO) di mulai dari phasa S, R, T.
d. Untuk antisipasi ketidak cukupan waktu pemadaman, maka perlu dibuat prioritas pemeliharaan yaitu dengan mengutamakan terlebih dahulu pada komponen utama (trafo, CO, Arrester, NH Fuse) atau komponen lain yang hanya dapat dikerjakan dengan pembebasan tegangan.
6-2-5-5 SOP Pelaksanaan Dengan Memadamkan Trafo 1) Lightning Arrester
Bila arrester masih terpasang sebelum CO, pindah arrester tersebut setelah Cut Out dengan memakai dudukan kanal NP8 – 2.500 mm (bila perlu siapkan kanal sendiri untuk praktisnya pelaksanaan), hal ini untuk mempercepat penanganan gangguan SUTM yang disebabkan oleh kegagalan lightning arrester.
Tabel 6-2. Tabel Daya dan Arus Fuse Link
No. Daya (kVA)
Arus(A)
Fuse LinkType K(A) No. Daya
(kVA)Arus (A)
Fuse LinkType K (A)
1 1 x 25 1,25 2 9 3 x 50 4,33 5 2 1 x 32 1,6 2 10 3 x 64 5,54 5 3 1 x 37,5 1,88 2 11 50 1,44 2 4 1 x 50 2,5 3 12 100 2,89 3 5 1 x 64 3,2 3 13 160 4,65 5 6 3 x 25 2,17 3 14 200 5,77 6 7 3 x 32 2,77 3 15 250 7,22 6 8 3 x 37,5 3,25 3 16 315 9,09 8
2) Fuse Cut Out (CO)
Jumper CO sisi atas disesuaikan dengan konduktor SUTM (TC aluminium 25 mm2 konektor ke Jaringan dengan CCO dan ujung ke terminal CO dengan SKAT3).
Jumper CO bagian bawah (ke trafo) diperbaiki/dipasang SKT 3, bila perlu ganti dengan NYAF 50 mm2.
Periksa kembali mur baut pada terminalnya, kencangkan bila perlu. Sesuaikan penggunaan fuse link seperti tabel 6.2.
Saklar dan Pengaman
313
2.1) Mengganti Fuse Cut Out (CO) Sesuai dengan namanya Fuse Cut Out, maka pada saat elemen
lebur (kawat lumer) putus karena kelebihan beban (over load), maka rumah sekring akan terbuka, sehingga tampak dari jauh rumah sekring tersebut menggantung keluar. Karena rumah sekring menggantung pada pengait (bagian bawah), maka bisa diambil dengan mengguna-kan galah pengaman. Sampai di bawah sekring lumer diganti, selanjutnya rumah sekring di pasang lagi pada gantungan dan ujungnya di dorong masuk ke klem(terminal) bagian atas. Cara memasukkan CO ini setelah gangguan selesai diatasi dan dimasukkan pada kondisi tidak berbeban. Selanjutnya beban disisi sekunder dimasukkan per kelompok grup.
3) Transformator
Minyak trafo ambil 1 botol melalui bawah, untuk test minyai dan tambah bila level minyak dibawah batas minimum melalui atas.
Bushing primer, bersihkan dengan sakapenk, periksa, kencangkan mur bila perlu/ganti bila rusak (untuk isolator yang di pasang arching horn dari kawat baja 10 mm2 atur jarak sparking rod selebar 13 cm, sesuai I.E.C.715A 1962 & SPLN 002/0ST/73).
Bushing sekunder bersihkan dengan sakapen, pasang plat tembaga (cooper) 4 x 4 x 90 mm untuk daya trafo 160 kVA, periksa kencangkan mur bila perlu ganti yang rusak.
Tap Changer periksa mekaniknya dan catat posisi tap changer (posisikan tap changer pada trafo beban kosong tegangan sekunder antara phas – nol 231 Volt).
Body trafo periksa, bersihkan/bila berkaratan cat total dengan kuwas (Cat Emco warna abu-abu).
Packing periksa kencangkan bila perlu/ganti packing bila rembes/bocor.
Grounding titik netral trafo periksa, ukur tahanan pentanahan, bila hasil pengukuran > 5 ohm tambah ground rod 2,5 meter (paralel).
4) LV Panel
LV Panel periksa, bersihkan, perbaiki/las bagian yang kropos dan cat kembali sesusai standart (termasuk perbaikan engsel & grendel pintu besi diberi grease/gemuk), bila rusak tidak bisa diperbaiki ganti dengan yang baru.
Saklar Utama periksa, kencangkan mur baut bila perlu dan beri vaselin putih pada kontaknya.
NH Fuse periksa, sesuaikan rating arus dengan daya trafo dan arus beban line (sesuai tabel 6.3).
Saklar dan Pengaman
314
Fuse Holder periksa/ganti bila rusak, kencangkan mur baut bila perlu dan beri vaselin putih pada kontaknya, bila ada grease (gemuk) bersihkan dulu dengan cleaner.
Sepatu kabel periksa dan ganti sepatu kabel bila rusak atau kondisi ujung kabel masuk (fudeng) trafo maupun kabel keluar ke JTR terbakar, disesuaikan dengan jenis (CU/AL) dengan bimetal yang sama dan ukuran konductor.
Kunci HS/LS periksa/bila macet semprot dengan pembersih (contac cleaner).
Grounding body LV panel, body trafo & lightning arrester periksa/ukur tahanan pentanahan/pasang groun rod 2,5 meter (II) bila tahanan tanahnya > 5 ohm.
Tabel 6-3. Tabel Daya dan Arus Fuse Link
No Daya (kVA)
Arus (A)
Fuse Link Type K (A) No Daya
(kVA)Arus (A)
Fuse Link Type K (A)
1 1 x 25 113,6 80 9 3 x 50 227,3 160
2 1 x 32 145,5 100 10 3 x 64 290,9 225
3 1 x 37,5 170,5 125 11 50 75,8 60
4 1 x 50 227,3 160 12 100 151,5 125
5 1 x 64 290,9 200 13 160 242,4 200
6 3 x 25 113,6 80 14 200 303 250
7 3 x 32 145,5 100 15 250 378,8 300
8 3 x 37,5 170,5 125 16 315 477,3 400
5) SUTR
Sambungkan out going ke JTR periksa/bila menggunakan percing konektor ganti dengan joint bimetal/disesuaikan dengan jenis conductor.
Ujung SUTR periksa, bila belum terpasang ground rod pasang ground rod 1,5 meter.
Gambar SUTR lengkap dengan SR per gardu.
Penggantian material harus dilaporkan pengawas PLN, bila material disediakan rekanan maka harus ada jaminan kualitas selama 1 tahun.
6) Pengoperasian Kembali Setelah semua pekerjaan selesai dilaksanakan, sebelum pengisian
tegangan maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :
a. Lepas semua grounding yang terpasang.
Saklar dan Pengaman
315
b. Lakukan pengecekan secara visual, apakah semua peralatan sudah terpasang dengan baik dan yakinkan tidak ada lagi peralatan kerja yang tertinggal.
c. Masukkan Fuse Cut Out satu persatu mulai dari phasa S, R kemuadian T.
d. Ukur tegangan masuk di LV panel antara phasa-phasa, phasa – netral, bila normal lakukan pembebanan trafo.
e. Masukkan skaklar utama (helboom), bila terpasang. f. Pembebanan trafo dengan memasukkan NH fuse jurusan satu persatu
mulai phasa s, r, t. g. Ukur parameter-parameter tegangan, arus dan temperatur mur baut
NH fuse, koneksi/sambungan. h. Bila semua telah selesai dilakukan, dari pengamatan visual dan
pengukuran tidak ada kelainan, maka pintu LV panel dapat ditutup kemudian dikunci dan pekerjaan dinyatakan selesai.
6-2-5-6 Pemeliharaan GTT Tanpa Memadamkan Trafo Pekerjaan pemeliharaan GTT yang tidak memerlukan padam total
adalah, hanya pemeliharaan yang sifatnya ringan, pekerjaan tersebut meliputi : a) Penambahan grounding (tambah ground rod). b) Penggantian joint kabel keluar dengan JTR (padam satu line JTR),
sebelum pelaksanaan pekerjaan perlu pemberitahuan pemadaman lewat media massa.
c) Pengelasan/pengecatan bagian luar LV Panel. d) Bila pekerjaan selesai cek kembali hasil pekerjaan tersebut secara
visual, mekanik dan yakinkan bahwa pekerjaan tersebut sudah benar dan baik, bila pekerjaan memerlukan pemadaman salah satu line jurusan, pastikan bahwa line jurusan tersebut sudah aman, bila aman masukkan NH fuse jurusan satu persatu mulai dari phasa 2, r kemudian t. Ukur tegangan antara phasa-phasa dan phasa–nol, bila kondisi
normal tutup pintu LV panel kemudian dikunci dan pekerjaan dinyatakan selesai. 6-3 Saklar dan Fuse
1. Fuse pada Papan Hubung Bagi Tegangan Rendah 2. Semi Automatic Change Over (SACO ) pada jaringan tegangan
rendah 3. Fuse Cut Out (CO) pada saluran udara tegangan menengah (SUTM) 4. Poletop Switch (PTS) dan Poletop Load Break Switch (LBS) 5. Penutup Balik Otomatik (PBO) dan Saklar Semi Otomatik (SSO) 6. Automatic Voltage Regulator (AVR) dan Capasitor Voltage Regulator
(CVR)
Saklar dan Pengaman
316
6-3-1 Load Break Switch (LBS) Swich pemutus beban (Load Break Switch, LBS) merupakan saklar
atau pemutus arus tiga fase untuk penempatan di luar ruas pada tiang pancang, yang dikendalikan secara elektronis. Switch dengan penempatan di atas tiang pancang ini dioptimalkan melalui control jarak jauh dan skema otomatisasi. Swich pemutus beban juga merupakan sebuah sistem penginterupsi hampa yang terisolasi oleh gas SF6 dalam sebuah tangki baja anti karat dan disegel. Sistem kabelnya yang full-insulated dan sistem pemasangan pada tiang pancang yang sederhana yang membuat proses instalasi lebih cepat dengan biaya yang rendah. Sistem pengendalian elektroniknya ditempatkan pada sebuah kotak pengendali yang terbuat dari baja anti karat sehingga dapat digunakan dalam berbagai kondisi lingkungan. Panel pengendali (user-friendly) dan tahan segala kondisi cuac. Sistem monitoring dan pengendalian jarak jauh juga dapat ditambahkan tanpa perlu menambahkan Remote Terminal Unit (RTU).
Pada umumnya versi-versi peralatan terdiri dari: Pole Top Load Break Switch Pole Top Control Cubicle Control & Protection Module
Dokumen-dokumen yang terkait antara lain:
Window Switchgear Operating Sistem (WSOS) Tes and Training Set (TTS) Database Access Protocol (DAP) Specific Telemetry Protocol Implementations Panel Kontrol Jarak Jauh Workshop Field dan Test Procedures Prosedur Penggantian CAPM
Versi-Versi Peralatan mencakup Contact Close dari penerimaan perintah tutup <1.2 sec dan Contact Open sejak diterimanya perintah buka <1.2 sec. Tegangan Line Maksimum pada Swicthgear Ratings antara 12 atau 24kV dengan arus kontinyu 630 A RMS. Media Isolasi Gas SF6 dengan tekanan operasional gas SF6 pada suhu 20 C adalah 200kPa Gauge. Pengoperasian secara manual dapat dilakukan secara independent oleh operator. Tekanan untuk mengoperasikan tuas Max 20 kg. Switch pemutus beban dilengkapi dengan bushing boots elastomeric untuk ruang terbuka. Boots tersebut dapat menampung kabel berisolasi dengan ukuran diameter antara 16 – 32 mm dan akan menghasilkan sistem yang terisolir penuh. Kabel pre-cut yang telah diberi terminal dapat digunakan langsung untuk bushing switch Pemutus Beban dan telah memenuhi persyaratan yang sesuai dengan peralatan tersebut. Namun demikian, untuk kabel, dapat menggunakan yang telah disediakan oleh peralatan tersebut sepanjang masih memenuhi spesifikasi yang ditentukan.
Saklar dan Pengaman
317
Kabel standar yang digunakan sebagai berikut:
Tabel 6-4. Kabel standar
Lug Size Stranding Material Rating
240 19/4.01 Aluminium 630 185 19/3.5 Aluminium 400 80 7/3.75 Aluminium 250
Konstruksi dan Operasi Load Break Switch dan Sectionaliser diuraikan
sebagai berikut. Load Break Swicth menggunakan puffer interrupter di dalam sebuah tangki baja anti karat yang dilas penuh yang diisi dengan gas SF6. Interrupter tersebut diletakkan secara berkelompok dan digerakkan oleh mekanisme pegas. Ini dioperasikan baik secara manual maupun dengan sebuah motor DC dalam kompartemen motor di bawah tangki. Listrik motor berasal dari batere-batere 24V dalam ruang kontrol. Transformer-transformer arus dipasang di dalam tangki dan dihubungkan ke elemen-elemen elektronik untuk memberikan indikasi gangguan dan line measurement. Terdapat bushing-bushing epoksi dengan transformer tegangan kapasitif, ini terhubung ke elemen-elemen elektronik untuk memberikan line sensing dan pengukuran. Elemen-elemen elektronik kontrol terletak dalam ruang kontrol memiliki standar yang sama yang digunakan untuk mengoperasikan swicthgear intelijen, yang dihubungkan ke swicthgear dengan kabel kontrol yang dimasukkan ke Swicth Cable Entry Module (SCEM) yang terletak di dalam kompartemen motor. 6-3-1-1 Fitur-fitur Swicthgear Instalasi penting dan fitur-fitur operator dari load break swicth (Gambar 6-19), yang meliputi:
Mounting bracket yang cocok untuk pemasangan semua jenis kutup daya. Mounting bracket ini dipasang ke kutup sebelum hoisting load break switch.
Poin-poin pengangkatan to hoist Load Breaket Switch ke dalam posisi untuk dikancing dengan baut ke bracket.
Hubungan tegangan tinggi dibuat dengan kabel berisolasi yang diterminasi pada bushing-bushing epoksi. Kabel dan bushing-bushing ditutup dengan boot elastomerik yang terisi dengan lemak silicon utnuk menciptakan sistem isolasi.
Penangkal arus kejutan bisa dipasang pada lubang-lubang yang tersedia atau pada kutub. Jika dipasang ditempat lain maka penangkal arus dipasang pada tangki Load Break Switch.
Sebuah earth bolt M12 disediakan untuk meletakkan load break switch. Jika terjadi internal arc fault, sebuah vent sisi kutup tangki load break
pecah untuk memberikan ventilasi bagi tekanan yang berlebihan. Ini menghilangkan resiko ledakan atau lepas dari kutub daya dank arena
Saklar dan Pengaman
318
unit tersebut tidak berisi minyak, maka bahaya kebakaran bisa dihindari.
Sebuah lengan operasi manual pada sisi yang paling lauh dari kutub membiarkan operasi hoolstick dari tanah. Dengan menarik sisi lengan yang tepat maka load break switch bisaditrip atau ditutup. Mekanisme ini “tergantung pada operator: sehingga tidak ada masalah seberapa cepat atau lambat lengan tersebut digerakkan oleh operator.
Indikator-indikator posisiload break switch disediakan di bagian bawah dan pada lengan operasi.
Sebuah counter operasi-operasi mekanis bisa dilihat melalui jendela pada bagian bawah kompartemen motor.
Kunci untuk mekanisme load break switch disediakan dengan menarik turun gagang manual loack dengan sebuah hookstick. Saat terkunci mekanisme tidak bisa trip atau close baik secara mekanisme atau secara elektrik.
Status interloack mekanis low gas ditunjukkan pada sisi bawah load break switch. Jika gas low maka sebuah penutup mengayun ke samping untuk mengekspos tanda merah low gas warning. Mekanisme juga dikunci secara mekanis sehingga tidak bisa trip atau close.
Gambar 6-19. Detail Load Break Switch
Saklar dan Pengaman
319
6-3-1-2 Sensor Tekanan SF6. Load break switch menggabungkan dua sensor tekanan yang memonitor tekanan gas SF6. Satu sensor dimonitor oleh elemen-elemen elektronik control dan digunakan untuk menampilkan tekanan gas panel control operator. Jika tekanan gas jatuh di bawah ambang yang telah diset maka indikasi rendah tekanan SF6 ditunjukkan pada panel kontrol operator (SF6 Pressure Low) dan semua operasi elektrik dikunci elektronik. Ambang untuk deteksi tekanan rendah dikompensasi dengan suhu.
Sensor kedua bersifat mekanis dan mengunci semua operasi jika tekanan gas hilang. Pemicuan interlock ini terindikasi ketika muncul tanda tekanan rendah yang berwarna merah pada sisi bawah kompartemen motor. Jika sudah dipicu interlock hanya bisa direset dengan prosedur untuk pengisian ulang gas pada swicth. Interlock gas ini hanya merupakan alat-alat pendukung. Operator harus selalu memeriksa tampilan tekanan gas dalam ruang kontrol dan indikator tekanan gas rendah sebelum operasi load break switch.
6-3-1-3 Memori Switchgear SCEM di dalam kompartemen motor memiliki sebuah memori
elektronik untuk menyimpan informasi tentang unit tersebut. Informasi ini meliputi nomor seri, breaking rating, continuous current rating, jumlah operasi mekanis, jumlah operasi mekanis , tegangan terukur, dan sisa umur kontak (per fasa) yang kesemuanya tersedia pada tampilan operator. Yang perlu mendapat perhatian bahwa counter operasi-operasi mekanis pada bagian bawah load break switch bisa berada di luar jalur ketika hitungan operasi disimpan dalam memori jika switch dioperasikan secara manual tanpa koneksi dan power up ruang kontrol. Demikian pula, umur kontak pada memori switchgear bisa tidak benar jika operasi switching manual dilakukan tanpa ruang kontrol terhubung dan di power up.
6-3-1-4 Umur Kontak Puffer interrupter dalam load break switch memiliki rating tugas yang
diberikan pada Bagian 3. elemen-elemen elektronik kontrol mengukur making/breaking current setiap saat load break switch beroperasi. Arus terukur ini digunakan untuk menghitung jumlah pemakaian kontak yang telah dialami setiap interrupter dan sisa umur kontakpun diupdate.
Sisa umur kontak disimpan dalam memori switchgear dan dapat ditampilkan dalam ruang kontrol. Jika sisa umur kontak mencapai nol pada fasa manapun maka load break switch harus diperbaharui.
Karena breaking current aktual diukur dan sebagian besar beban benar-benar lebih rendah dari line current maksimum, maka metode pemantauan ini diharapkan akan memberikan umur operasi yang lebih panjang dari metode penghitung operasi sederhana.
Saklar dan Pengaman
320
6-3-1-5 Penyambung ke Kontak Kontrol Load break switch dihubungkan ke ruang kontrol dengan sebuah kabel kontrol. Kabel ini dimasukkan ke kompartemen motor pada bagian bawah switchgear. Kabel kontrol membawa hubungan-hubungan berikut ini :
Signal-signal operasi motor
Travel switches yang memantau posisi kontak-kontak (satu switch yang menandakan close dan lainnya menandakan open) dan posisi gas interlock/interlock mekanis.
Transformer-transformer arus dan layar-layar tegangan yang dimasukkan dalam bushing-bushing yang mengirimkan signal ke elemen-elemen elektronik untuk memonitor line current arus bumi dan tegangan fasa/bumi. Jika kabel kontrol dilepas (pada salah satu ujungnya) maka sigmal-sigmal ini secara otomatis dipersingkat oleh elemen arus di dalam load break switch.
Signal-signal untuk membaca dan menulis memori switch.
6-3-1-6 Kontak Kontrol dan Panel Peralatan Kontak control dirancang untuk tujuan pengoperasian untuk tiang
pancang di ruang terbuka. Kontak kontrol tersebut mempunyai jendela ber-engsel yang dapat diakses oleh petugas operasional dalam segala cuaca sebuah pintu masuk untuk staf pemeliharaan.
Baik pintu maupun jendela tersebut dapat digembok untuk demi keamanan dan pintu bisa dipindahkan jika perlu. Gambar 6-20 menunjukkan dimensi ruang control. Di dalam cover terdapat sebuah panel peralatan dengan ciri-ciri utama berikut.
Ruang kabel-kabel menampung transformer-transformer kabel LV dan sakelar pemutus untuk batere dan suplai Bantu.
Ruang elemen-elemen elektronik menampung Modul Kontrol dan Proteksi (CAPM) dan Sub-Sistem Panel Operator (OPS). Ruang ini disegel untuk melindungi elemen-elemen elektronik dari polusi udara.
Ruang batere menampung 2 batere 12 Volt.
Slot untuk radio digunakan untuk menaikkan radio komunikasi, modem atau kartu IOEX. Nampan ini tergantung ke bawah untuk mengekpos radio/modem dan dapat dilepaskan untuk pemasangan radio.modem.
Modul Entri Kabel Kontrol menyediakan terminasi dan penyaringan untuk kabel control, modul ini ditempatkan di belakang sebuah panel yang dapat dipindahkan.
Kabel control yang masuk dihubungkan ke P1 dari CCEM, alat pemasang kabel N03-505 dihubungkan ke P2 dari CCEM.
Saklar dan Pengaman
321
Kompartemen pemanas untuk pemanas ruang control.
Di tengah panel peralatan terdapat sebuah pipa karet untuk saluran kabel yang menampung sistem kabel internal. Panel peralatan dapat dipindahkan dengan melepaskan hubungan-hubungan eksternal dan baut-baut ini bisa dilakukan di lapangan jika dianggap perlu untuk mengganti keseluruhan panel peralatan. Demikian pula mungkin lebih mudah untuk mengganti seluruh ruang control. Panel peralatan diatur sedemikian sehingga komponen-komponen yang sensitif terdapat panas, batere ditempatkan di bagian bawah dekat tempat masuknya udara. Pada keadaan-keadaan tropis, pengaturan ini menjamin batere dapat bertahan dalam beberapa derajat suhu sekitar setiap saat dan dengan demikian memaksimalkan umur batere. Di samping bagian yang paling menimbulkan panas, suplai listrik ditempatkan di bagian atas ruang sehingga dapat meminimalkan dampak pemanasan pada bagian-bagian lain.
6-3-1-7 Penyegelan dan Kondensasi Semua lubang angin dipasang saringan untuk mencegah masuknya
binatang-binatang kecil dan pintunya disegel dengan pita busa yang dapat diganti. Segel penuh terhadap air pada semua kondisi tidak diharapkan, misalnya selama operasi pada waktu hujan dengan jendela dalam keadaan terbuka. Oleh karena itu rancangannya dibuat sedemikian rupa sehingga jika ada air yang masuk, air itu akan terus mengalir ke bawah dan keluar tanpa mengganggu bagian-bagian elektrik atau komponen-komponen elektronik. Keadaan ruang memiliki sistem pemanas dan ventilasi yang baik sehingga menjamin tidak terjadinya kelembaban. Penggunaan baja anti karat dan bahan-bahan tahan air menjamin kelembaban yang terjadi tidak menimbulkan dampak yang merusak.
Kondensasi dapat terjadi pada beberapa keadaan atmosfir seperti badai tropis. Tetapi karena rancangan yang memiliki isolasi dan ventilasi yang baik, kondensasi akan terjadi pada permukaan-permukaan logam tanpa memberikan dampak yang berarti. Air akan keluar dengan lancar. Kondensasi akan keluar ke bawah dan kering oleh karena ada sistem ventilasi dan pemanasan.
6-3-1-8 Sumber Tenaga Tambahan Supply tenaga tambahan digunakan oleh kotak control untuk mempertahankan daya pada batere lead-acid yang telah disegel yang digunakan untuk tenaga cadangan saat tenaga tambahan padam. Tenaga tambahan berasal dari salah satu dari dua sumber berikut ini :
Suplain LV disediakan oleh utility. Sehingga terhubung ke kotak control. Dalam hal ini ruang control dipasang dengan sebuah transformer yang cocok dan plat namanya menunjukkan tegangan supply tambahan yang diperlukan.
Saklar dan Pengaman
322
Supply kabel HV ke transformer tegangan (VT), dipasang pada kutub dan dihubungkan ke dalam Swicth Cabel Entry Module (SCEM) dalam kompartemen motor. Ini disebut HV supply. Dalam hal ini plat rating pada transformer mengindikasikan rating tegangan.
Bagian 6 memberikan rincian tentang earthing dan hubungan listrik bantu.
6-3-1-10 Slot untuk memasukkan kabel Semua kabel masuk ke ruang control melalui bagian bawah seperti
terlihat pada Gambar 6-22. Saluran masuk kabel disediakan untuk : Kabel control dari recloser yang disambungkan ke connector P1 di
dasar ruang batere. Satu atau dua mains supply yang di belakang panel peralatan. Dua
lubang 20 mm yang disediakan untuk entri kabel. Kabel komunikasi/antenna radio, lubang 16 mm disediakan untuk
entri kabel.
6-3-1-11 Tempat Injeksi Arus Sebuah konektor enam arah yang disebut “Poin Injeksi Arus” terletak
pada kompartemen utama. Konektor ini digunakan dengan Test and Training Set (TTS) untuk melakukan injeksi sekunder sementara switchgear terhubung. Proses ini membuat injeksi peralatan tanpa diskoneksi.
6-3-1-12 Indikator Gangguan Indikator gangguan eksternal pilihan dapat dipasang pada bagian
atas kontrol atas ruang kontrol. Ini adalah xenon stobe yang akan menyala jika elemen elektronik kontrol mendeteksi adanya gangguan pada Load Break Switch. Setelah suatu event Maximum Current diadakan (di mana gangguan telah berakhir) arus-arus line dipantau selama satu detik. Jika arus pada ketiga fasa jatuh ke nol selama waktu ini maka event Supply Interrupt akan diadakan yang mengindikasikan pembukaan sebuah pemutus arus hulu. Arus nol ditentukan sebagai ambang untuk tampil pada panel kontrol operator. Sebuah Supply Interruption Current ditambah setiap saat suatu event Supply Interrupt terjadi. Current tersebut diset ke nol jika line-nya bebas dari gangguan selama waktu reclaim yang dikonfigurasikan oleh user (Reclaim Time 30s) sementara load break switch tertutup. Dengan cara ini Supply Interruption Counter menghitung operasi pemutus arus hulu (atau reclose) dalam suatu urutan gangguan. Nilai Supply Interruption Counter ditunjukkan dalam event Supply Interrupt. Ketika reclaim timer telah lewat waktu berlalu maka suatu event Reclaim Expired akan diadakan.
Saklar dan Pengaman
323
Gambar 6-20. Ruang Kontak Kontrol Load break switch
Gambar 6-21. Panel Perlengkapan Load break switch
Saklar dan Pengaman
324
Jika arus jatuh ke nol hanya pada fasa yang mengalami gangguan (mungkin karena operasi sekring) maka suatu event Phase Interrupt diadakan hanya untuk fasa tersebut dan Supply Interruption Counter tidak ditambah.
Elemen elektronik control memantau layar-layar tegangan yang ada di dalam H.V bushings untuk menentukan apakah bushing-bushing dalam keadaan hidup. Live line ditunjukkan pada tampilan real time ketika tegangan fasa/tanah bushing melebihi ambang yang dikonfigurasikan oleh user. Status live line digunakan untuk membangkitkan event-event saat kehilangan supply.
Untuk menentukan apakah supplynya hidup, maka status live line harus ditambah pada ke tiga bushing pada sisi line selama waktu yang ditetapkan oleh user.
Event-event deteksi gangguan yang digambarkan di atas bisa mengeset bendera-bendera deteksi dalam memori microprocesor elektronik kontrol. Event-event ini digunakan untuk mengindikasikan gangguan yang menggunakan indikator gangguan eksternal pilihan.
User bisa mengkonfigurasikan sistem sehingga bendera-bendera diset hanya dengan event-event Supply Interrupt dan Phase Interrupt (interrupted fault). Setting pertama ini akan mengindikasikan semua gangguan. Setting kedua hanya akan mengindikasikan gangguan-gangguan yang telah diinterupsi dengan suatu sekring hulu atau Circuit Breaker. Bendera-bendera ini mungkin tersedia untuk telemetry pada sebuah komputer pengawas jika didukung dengan protocol telemetry yang dipasang dalam CAPM.
Load Break Switch dilengkapi dengan automatic sectionalising logic. Sectionalising logic membuka Load Break Switch selama waktu matinya circuit breaker hulu setelah trip dan recluse sebanyak jumlah yang dikonfigurasikan oleh recluser. Waktu mati circuit breaker hulu harus diset menjadi lebih besar dari 1,2 detik.
Keistimewaan sectionaliser bisa dimungkinkan atau tidak dimungkinkan oleh operator dari panel kontrol operator. Sectionaliser menggunakan supply Interruption Counter untuk menghitung trip dari sebuah circuit breaker hulu selama suatu fault sequence. Ketika counter tersebut mencapai nilai yang dikonfigurasikan user Load Break Switch. Trip secara otomatis. Ini menimbulkan event sectionaliser trip.
6-3-2 Pemasangan, Pembongkaran dan Pengecekan Masing-masing krat berisi: Load Break Switch dengan kutup bagian atas Ruang kontrol (yang biasanya menampung dua batrei kecuali telah
dibuat pengaturan dimana batrerenya dikirim secara terpisah) Kabel kontrol
Saklar dan Pengaman
325
Enam cable tail baik dengan thereded lug untuk disekrup ke dalam bushing secatra langsung atau dengan lug datar untuk dipasang pada piringan yang telah terpasang pada bushing-bushing.
Enam bushung boot, tabung lemak silikion dan spanner pemasang boot
Pole mounting bracket Penjepit untuk memasang switch ke pole mounting bracket
Alat-alat yang diperlukan pada pembongkaran: Obeng dan kunci pembuka mur 3/16 hex untuk membuka krat. Dua alat penahan dan derek dengan daya angkut 200 kg untuk
mengangkat saklar pemutus arus. Pindahan bagian atas krat dan keluarkan kabek-kabel HV, kabel
kontrol dan semua item di bagian atas krat. Simpan di tempat yang bersih dan kering.
Buka kayu-kayu penyangga, pasang alat penahan pada titik-titik pengangkatan pada Load Break Switch dan keluarkan Load Break Switch untuk diletakkan di atas tanah dengan menggunakan derek.
Angkat ruang kontrol dan letakkan di tempat yang bersih. Keluarkan kotak-kotak aksesoris dan letakkan di tempat yang bersih
dan kering. Buka sekrup dan keluarkan mounting bracket dan letakkan di tanah.
6-3-2-1 Testing dan Konfigurasi Uji coba dapat dilakukan di lokasi atau dibengkel sesuai dengan
keinginan. Bongkar kratnya dan letakkan kabel-kabel HV dan kabel kontrol di
tempat yang bersih dan aman agar tidak rusak dan kotor. Buat ground connection sementara antara ruang kontrol dan saklar pemutus arus, yang hanya membutuhkan kabel tembaga 1mm2.
Pindahkan plat penutup akses pada ruang motor dan sambungkan kabel kontrol ke P1 di Switch Cable Entry Module (SCEM).
Matikan listrik di kotak kontrol dengan mematikan seluruh MCB.Harus diperhatikan bahwa hal ini harus dilakukan ketika menyambungkan atau memutuskan kabel kontrol dari kotak kontrol. Pindahkan penutup kotak kontrol dan masukkan kabel kontrol tersebut dan sambungkan ke konektor P1 pada Control Cable Entry Module (CCEM).
Jika ruang kontrol tidak dilengkapi untuk LV auxiliary supply (karena sebuah suplai HV terpadu adalah untuk dihubungkan ke Load Break Switch di lokasi ) maka bisa dibuat suplai bantu sementara dengan menghubungkan suplai AC 24 V terpadu dan terisolasi atau DC 32 Volt 24 VAC atau 32 VDC antara terminal 2 dan 3 dari blok terminal pada mains compartment. Batere 36 V terisolasi adalah cara yang
Saklar dan Pengaman
326
baik. Perhatikan bahwa ini terhubung langsung ke CAPM dan tidak dapat dimatikan dengan pemutus arus ruang kontrol.
Hidupkan batere dan pemutus arus suplai bantu pada bagian atas ruang kontrol dan lakukan uji coba berikut:
Trip dan close manual dari saklar pemutus arus. Tes isulasi koneksi-koneksi tegangan tinggi ke bumi untuk mengecek
kerusakan-kerusakan pada saat pengiriman pada sisi tegangan dari saklar pemutus arus.
Mengkonfigurasi setting-setting proteksi. Lakukan injeksi arus primer sesuai persyaratan Lakukan injeksi arus sekunder sesuai persyaratan dengan
menggunakan tesk and training Set (TTS) Plat radio/modem dapat dilepaskan sekrupnya dan radio atau
modem dapat dipasang, dihubungkan dan dicoba sesuai peryaratan. Jika Load Break Switch telah disambungkan ke powered up cubicle
contor maka jangan mencabut atau mematikan ruang control sebelum panel operator berhenti berkedip.
Ikuti perintah perawatan batere yang diberikan dan perhatikan bahwa memasang batere dengan reverse polarity akan menyebabkan kerusakan pada sistem-sistem elektro elektronik.
Mungkin untuk sementara ini lebih baik memasang cable tails dan penangkal arus kejutan ke switchgear.
6-3-2-2 Pengangkutan ke Lokasi Jika pembongkaran dan pengujian dilakukan di bengkel maka
pemutus arus dan ruang kontrol harus diangkut ke lokasi. Penting untuk dilakukan langkah-langkah berikut ini: Matikan semua pemutusan ruang kontrol dan cabut semua supply
daya bantu. Cabut kabel kontrol dari pemutus arus dan ruang kontrol dan letakkan kembali platpenutup pada bagian dasar pemutus arus.
Pindahkan batere dari ruang kontrol untuk diangkat secara terpisah atau amankan batere dalam ruang kontrol.
Angkat saklar pemutus, ruang kontrol dan semua bagian dengan cara yang baik dan aman.
6-3-2-3 Memasang dan Mencabut Kabel Kontrol Perhatikan bahwa kabel kontrol tidak simetris, plat ujung dengan
sudut mitred terhubung ke switchgear dan dubutuhkan teknik yang benar untuk menghubungkan dan melepaskan kabel kontrol. Lihat Gambar 6-25 dan 6-26.
Saklar dan Pengaman
327
Untuk menusuk kontak : pegang tusuk kontak pada sisi panjang, cek orientasinya, letakkan dengan pelan-pelan soket/tampuk dan dorong agak kuat. Cek apakah sudah terkuncicaranya yaitu dengan menggoyang-goyang kontak itu. Jika kontaknya tidak bisa didorong dengan kekuatan sedang maka posisinya belum benar. Tetapi jangan dorong terlalu keras.
Untuk mencabut kontak: pegang tusuk kontak pada sisi-sisi pendek pegang dengan cengkeraman yang keras untuk melepaskan klip-klip yang ada di dalam yang tidak terlihat. Kemudian digoyang-goyang untuk melepaskan klip-klip tersebut kemudian cabet kontaknya jangan mencabut kontak dengan menarik kabelnya.
6-3-3 Pengujian Load Break Switch Kabel-kabel HV disupply dalam dua bentuk: Dilengkapi dengan lug untuk dipasang pada ujung bushing (250 atau
400A). Dilengkapi dengan theaded termination yang disekrupkan ke dalam
bushing (630A).Untuk kedua bentuk tersebut prosedurnya adalah untuk memasang kabel pada bushing dan kemudian menutupnya dengan bushing boot seperti yang digambarkan pada bagian-bagian berikut (Lihat Gambar 6-27)
Perhatikan bahwa isi silikon sangat penting karena menjamin baut tersegel ke bushing dan tidak ada air yang masuk.
Gambar 6-22. Menghubungkan Kabel
Saklar dan Pengaman
329
Bushing disuplai dalam keadaan bersih dan dilindungi dengan kap busa. Pastikan tidak terjadi gangguan dan badan bushing konduktor tengah berlapis timah atau palm dalam keadaan bersih dan tidak ada kerusakan. Jika bushingnya kotor maka harus dibersihkan dengan spirtus meyil. Sikat atau gosok dengan kertas pasir untuk menghilangkan oksida.
Beri pelumas ada bushing dan konduktor dengan lemak silikon yang disediakan.
Bongkar cable tail dan bushing boots. Pastikan bahwa terminai kabel dan boot dalam keadaan bersih dan tidak ada kerusakan, jika perlu, bersihkan dengan spirtus metal.
Dorong bootnya lewat kabel sejauh kira-kira 1 meter dari termjinasi (beri sedikit pelumas pada ujung boot agar boot bisa dengan mudah didorong melalui kabel). Isi bushing boot dengan lemak silicon yang disediakan, mulai dari ujung closed end sampai kira-kira 60 mm dari
ujung lainnya pen end dari boot tersebut. Saat anda mengisi boot terus geser boot tersebut kebawah. Ini akan mendorong lemak ke dalam boot.
Untuk kabel-kabel dengan ujung spiral sekrup, masukkan ke dalam bushing dengan memutar seluruh cable tail. Kencangkan sampai 70Nm dengan menggunakan spanner di seluruh locknut yang terpasang. Hati-hati agar ini dilakukan dengan pelan-pelan.
Untuk kabel-kabel yang mempunyai lug pada ujungnya. Gorokkan pasta pesekat aluminium dan pasang lug itu pada bushing palm dengan baut yang tersedia dan kencangkan sampai 60Nm. boot kebawah sambil memutar-mutarkan bootnya. Pasang pada tempatnya dengan menggunakan cincin penjepit dan spanner yang tersedia. Dasar boot harus benar-benar duduk di atas tangki saklar pemutus. Selama proses pengepitan akan silikon akan keluar dari bagian atas boot tempat ujung kabel keluar. Ini hal yang biasa dan bisa dibantu dengan memasukkan obeng kecil ke dalam boot di sepanjang ujung kabel (cable tail). Lemak silikon juga akan keluar dari saklar dasar bushing. Ini hal yang biasa. Lap lemak silikon yang keluar itu dengan kain bersih. Perhatikan bahwa anda harus mendorong boot dengan keras agar boot bisa turun cukup jauh agar bisa terpasang dengan baik pada cincin penjepit.
Lumasi permukaan bushing, geser bushing Pada cuaca dingin anda harus mendorong sangat keras. Pemasangan boot ini paling baik dikerjakan oleh dua orang, satu orang mendorong dan lainnya memasang dan memutar cincin penjepit.
6-3-4 Pemasangan dan Penyambungan Surge Arrester Tersedia penyangga-penyangga untuk penangkal arus kejutan pada
kaki-kaki Load Break Switch.
Saklar dan Pengaman
330
Hubungan-hubungan dari penangkal arus kejutan ke cable tail bisa dibuat dengan mengupas isolasi cable tail dan menggunakan klem paralel atau tipe T untuk membuat koneksi ke cable tail. Cable tail memiliki pelindung terhadap air sehingga tidak diperlukan penahan air tambahan di mana isolasinya telah dibuka. Tetapi baik juga untuk membalut dengan pita pada sambungan untuk menjaga isolasi sistem kabel.
Gambar 6-25. Terminal TeganganTinggi
Gambar 6-26. Sambungan Suplai Tegangan Rendah
Saklar dan Pengaman
331
6-3-5 Pentanahan
Gambar 6-28 Menunjukkan pentanahan yang umum bagi semua instalasi. Sistem ini menghubungkan Load Break Switch dan penangkal arus secara langsung ke tanah melalui main earth bond yang terdiri dari sebuah konduktor tembaga paling kurang 70mm² kejutan-kejutan apapun akan mengalirmelalui saluran ini. Jangan menghubungkan penangkal arus kejutan dengan saluran yang berbeda, karena jika hal tersebut dilakukan akan mengakibatkan kerusakan pada elemen-elemen elektronik kontrol atau saklar pemutus arus.
Juga antena manapun harus dihubungkan ke saklar pemutus arus atau earth bond utama.
Ruang kontrol dihubungkan ke main earth bond dengan sebuah tee-off. Elemen-elemen elektronik ruang control terlindung secara internal dari perbedaan-perbedaan [potensial yang bisa terjadi antara
kerangka saklar pemutus arus dan kerangka ruang control sementara arus-arus kejutan mengalir turun melalui main earth bond.
Tidak diijinkan adanya koneksi-koneksi laun untuk menghubung-kan dari ruang control karena arus-arus kejutan juga akan melangalir melalui saluran-saluran itu. Pengaturan ini harus diikuti konduksi dan insulasi kutub-kutub listrik.
Gambar 6-27. Sambungan Kabel Ujung
Saklar dan Pengaman
332
Main earth bond harus dipisahkan secara fisik dari kabel karena di
sepanjang kutub listrik tersedia space yang maksimal. Ukurannya adalah 200 mm untuk kayu dan kutub konkrit dan 100 mm untuk kutub baja.
6-3-6 Listrik LV tambahan dari Saluran Utama Dimana LV mains dihubungkan ke ruang kontrol untuk menyediakan
listrik bantu maka hubungan tersebut harus menghubungkan sisi netral dari sistem LV ke sebuah tee-off dari main earth bond seperti ditunjukkan pada Gambar 6.32. Sebuah penangkal arus kejutan LV juga harus dipasang dari koneksi fasa LV ke tee-off ini.
Rancangan koneksi ini menghubungkan LV dan HV earth sehingga melindungi insulasi utama dari transformer supply bantu dalam ruang kontrol saat arus-arus kejutan sedang mengalir. Penangkal arus kejutan LV tambahan harus dipasang pada semua fasa LV lainnya (jika ada) untuk keseimbangan supply untuk pengguna lain yang terhubung ke sistem LV. Jika kondisi lokal atau aturan sistem kabel melarang bonding sistem-sistem LV dan HV dengan cara ini maka supply bantu ke ruang kontrol dari LV mains sistem tidak mungkin ada. Maka harus digunakan salah satu pengaturan alternatif yang dijelaskan di bawah ini.
Gambar 6-29 menunjukkan koneksi-koneksi jika transformer resmi disupply oleh utility. Gambar 6-29 juga menunjukkan bahwa transformator dan peralatan baja apapun dihubungkan ke tangki saklar peralatan di dalam ruang control.
Transformer tegangan tersedia baik di dalam atau diluar tangki saklar pemutus arus yang secara langsung terhubung ke dalam elemen-
Gambar 6-28. Suplai Tegangan Rendah dan Terminal Grounding
Saklar dan Pengaman
333
Gambar 6-29 Gabungan Kabel supplai dari Terminal Trafo
elemen elektronik kontrol. Ini disebut Integrated auxiliary Supply. Koneksi-koneksi ditunjukkan Gambar 6.29.
Transformer naik pada kutub daya dan terhubung ke dalam SCEM di dalam kompertemen motor dan Load Break Switch. Untuk menghubungkan sekunder transformer, plat akses dan salah satu blanking plug 20mm SCEM di pindahkan. Saluran kabel yang terpasang sebelumnya dengan sebuah cable gland melalui lubang dan amankan gland tersebut.
6-3-7 Perawatan
Perawatan dilakukan dengan menggunakan alat-alat mekanis dan teknisi listrik standar. Tidak diperlukan perawatan user terhadap mekanisme Switch pemutus beban. Switch pemutus beban harus diperbaharui jika tugas mekanik dan tugas pemutusan sudah melewati batasnya.
Setiap lima tahun bushing boot harus dicek, bila perlu dibersihkan dan pointer dan tuas juga dicek untuk memastikan perangkat tersebut bebas dari ganguan mekanis. Didaerah-daerah yang memiliki tingkat polusi lingkungan yang tinggi perlu dilakukan pembersihan yang lebih sering. Cek gas low alarm secara rutin agar tidak muncul pada panel kontrol operator. Jika terlihat gas low, maka isi kembali SF6 dengan menggunakan adaptor isi gas. Perawatan kotak pengendali diperlukan paling tidak setiap lima tahun. Memberisihkan ruang kontrol, khususnya atapnya dan bersihkan. Lubang-lubang jendela pada ruang kontrol harus dipastikan tidak tersumbat dan juga lubang-lubang pedingin dan saluran air di bagian dasar dalam keadaan terbuka. Saat tutupnya dipindahkan, pastikan bahwa kasa penahan
Saklar dan Pengaman
334
sarangan tidak terganggu oleh kotoran atau debu. Penggantian batere adalah sebagai berikut:
Matikan pemutus arus batere Cabut batere-batere dan gantikan dengan batere yang baru. Pastikan bahwa polaritasnya benar
Hidupkansaklar pemutus arus batere dan pastikan bahwa status Battery Normal tersimpan pada tampilan status sistem.
Pengecekan deteksi gangguan dan sectionaliser dilakukan sebagai berikut. Bypass dan isolasikan Load Break Switch dan lakukan uji injeksi primer untuk mencek fault detect dan operasi sectionaliser. Karet seal pintu juga perlu dicek apakah ada kerusakan atau pengerasan. Jika perlu ganti dengan segel yang baru. Batere diperkirakan akan memberikan penampilan yang baik selama periode lima tahun. Di beberapa lingkungan, suhu ruang kontrol yang terlampau tinggi bisa mengakibatkan periode penggantian batere yang lebih singkat. Jika telah digunakan, maka hanya sedikit perawatan yang diperlukan untuk batere. Prosedur penyimpanan dan kemungkinan-kemungkinan lainnya adalah sebagai berikut:
Batere harus disimpan pada suhu kurang dari 30ºC dan disiklus setiap enam bulan.Batere harus disimpan paling lama 1 tahun
Batere harus diganti sebelum digunakan jika belum disiklus selama tiga bulan.
Jika batere telah habis tegangannya dan dibiarkan lebih dari dua mjinggu tanpa diberi supply bantu ke ruang kontrol maka batere harus dikeluarkan, disiklus dan cek kapasitasnya sebelum digunakan kembali.
Untuk mensiklus batere discharge dengan rasistor 10 Ohm 115 Watt ke tegangan terminal 10V. Kemudian, isi kembali dengan supply DC pengaturan tegangan yang diset ke 13,8V, supply terbatas arus 3A akan tepat sekali.
6-3-8 Pengisian Kembali Gas SF6 untuk Switch Pemutus Beban
Pengisian ulang SF66 pemutus arus dilakukan dengan menggunakan
Gas Fill Adaptor (GFA) dan sebuah silinder SF6 ukuran D standar. Prosedur pengisian ulang adalah sebagai berikut:
Pindahkan kap dari katup isi gas pada sisi katub Load Break Switch Hubungkan adaptor isi gas ke silinder SF6 buka pelan-pelan katup
pada silinder untuk mengalirkan gas ke dalam selang. Tutup katup pada silinder SF6 .
Dorong cincin pada katup isi gas dan colokkan pasangan selang adaptor isi gas. Tekanan gas Load Break Switch sekarang akan terlihat pada pengukuran tekanan.
Buka katupnya pada bagian ukuran untuk melepaskan gas ke dalam saklar pemutus arus. Operasi ini akan dilakukan perlahan-lahan dan Anda harus berhati-hati agar tekanan pada saklar pemutus tidak
Saklar dan Pengaman
335
terlampau tinggi. Katup pelepasan dipasang pada adaptor isi gas untuk tujuan keamanan, namun tidak menjamin tidak melindungi saklar pemutus dari tekanan tinggi. Jika kelebihan gas dmasukkan dalam saklar pemutus maka dapat dikeluarkan dengan memutuskan hubungan adaptor isi gas dari silinder gas.
Isi ulang Load Break Switch sampai pada tekanan di bawah 200kPa pada pengukuran (gauge) terkoreksi oleh +/- 1kPa untuk setiap derajat Celsius di atas/di bawah 20ºC.
Cabut katup selang isi gas dengan medorong cincin pada katuip isi gas.
Pindahkan cincin ’O’ lama dari katup isi gas dan buang. Bersihkan tempat peletakan cincin ’O’ pada katup isi gas dan kap dengan kain bersih. Kencangkan kembali kapnya.
6-3-4-5 Pencarian Gangguan Gangguan hanya bisa terjadi pada salah satu di antara:
Saklar pemutus beban Kabel Kontrol Ruang Kontrol
Cara terbaik untuk menentukan bagian mana yang mengalami gangguan adalah dengan menggunakan Tesk and Trainig Set. Jika tidak tersedia Test and Training Set maka gunakan switchgear chec seperti yang disarankan di bawah ini dan gunakan teknik-teknik substitusi untuk menentukan dimana letak gangguan. Load Break Switch yang mengalami gangguan bisa dikembalikan ke pabrik untuk diperbaiki.
Kabel-kabel kontrol yang mengalami gangguan harus diganti. Ruang kontrol yang mengalami gangguan bisa dicek dan diperbaiki seperti petunjuk di bwah ini.
6-3-4-6 Pemeliharaan Switchgear dan Kabel Kontrol Hubungan-hubungan ke Load Break Switch tersedia pada SCEM
dalam kompartemen motor dan/atau di atas konektor kabel kontrol yang masuk P1 pada Control cable Entry Module (CCEM) bagian bawah ruang kontrol. Beberapa (tetapi tidak semua) koneksi ini secara sederhana bisa diuji dengan DVM. Ini bisa menunjukkan gangguan-gangguan Load Break Switch dengan uji yang sederhana.
Tabel di bawah ini bisa digunakan untuk mengecek swirchgear dan kabel kontrol. Uji ini harus dilakukan dengan kabel kontrol yang tersambung ke dalam switchgear dan ujung ruang kontrol tidak tersambung.
6-4 Pengaman Jaringan distribusi berfungsi menyalurkan tenaga listrik dari pusat
beban ke pihak pelanggan melalui jaringan listrik tegangan menengah dan tegangan rendah. Karena fungsinya tersebut maka keandalan menjadi faktor sangat penting, untuk itu jaringan distribusi dilengkapi dengan pengaman.
Saklar dan Pengaman
336
Ada tiga fungsi sistem pengaman, yaitu untuk: (i) mencegah atau membatasi kerusakan pada jaringan beserta peralatannya, (ii) menjaga keselamatan umum akibat gangguan listrik, dan (iii) meningkatkan kelangsungan atau kontinyuitas pelayanan kepada pelanggan.
Sistem pengaman yang baik harus mampu: (a) melakukan koordinasi dengan sistem TT (GI/transmisi/pembangkit), (b) mengamankan peralatan dari kerusakan dan gangguan, (c) membatasi kemungkinan terjadinya kecelakaan, (d) secepatnya dapat membebaskan pemadaman karena gangguan, (e) membatasi daerah yang mengalami pemadaman, dan (f) mengurangi frekuensi pemutusan tetap (permanen) karena gangguan. Di samping itu, setiap sistem atau alat pengaman harus mempunyai kepekaan, kecermatan dan kecepatan bereaksi yang baik.
Tabel 6-5.Panduan Pengujian Switchgear
Pin Tes Penggunaan Hasil Yang diharapkan
1-ve to 5+ve Resistance Motor Relay
10 to 15 kOhm (expect a long delay when taking this measurement because of a parallel capacitor)
2 to 5 DC Voltage
Integrated auxiliary supply tranformer (if fitted). This has been rectified internally so a DC full wave rectified signal is present
25 to 45 VDC measured with a true RMS meter when the transformer primary is energized.
3 to 5 Resistance Motor Relay 10 to 15 kOhm (expect a long delay when taking this measurement because of a parallel capacitor)
4 to 8 Resistance W phase CT 13 Ohm+/-3 Ohm 12 to 16 Resistance V phase CT 13 Ohm+/-3 Ohm 20 to 24 Resistance U phase CT 13 Ohm+/-3 Ohm
21 to 11 Resistance Auxilliary <5 Ohm when breaker is tripped >100kOhm when circuit breaker is closed
22 to 11 Resistance Auxilliary travel switch closed indicates circuit breaker is closed
<5 Ohm when circuit breaker is cloded >100kOhm when circuit breaker is tripped
6-4-1 Kepekaan (sensitivitas) Suatu pengaman bertugas mengamankan suatu alat atau bagian
tertentu dari sistem tenaga listrik, alat atau bagian sistem yang termasuk dalam jangkauan pengamanannya atau merupakan ‘daerah pengamanan’. Salah satu tugas suatu pengaman adalah mendeteksi adanya gangguan yang terjadi pada daerah pengamanannya dan harus memiliki kepekaan
Saklar dan Pengaman
337
untuk mendeteksi gangguan tersebut dengan rangsangan minimum, dan bila perlu men-trip-kan pemutus tenaga (pelebur) untuk memisahkan bagian sistem yang terganggu dengan bagian sistem yang sehat.
6-4-2 Kecermatan (Selektivitas) Selektivitas dari pengaman adalah suatu kualitas kecermatan pemilihan dalam mengadakan pengaman bagian yang terbuka dari suatu sistem, oleh karena terjadinya gangguan sekecil mungkin jika dapat tercapai maka pengaman demikian disebut pengaman yang selektif.
Pengaman hanya akan bekerja selama kondisi tidak normal atau gangguan yang terjadi di daerah pengamanannya dan tidak akan bekerja pada kondisi normal atau pada keadaan gangguan yang terjadi di luar daerah pengamannya. Gambar 6.30 memperlihatkan bahwa daerah-daerah yang berdekatan selalu saling menutupi bagian (overlap) hal ini memang perlu, karena jika tidak maka ada daerah yang dibiarkan tanpa pengaman atau disebut juga daerah mati (dead zone) jika terjadi gangguan di daerah overlap ini, maka mungkin kedua pengaman dari daerah bersangkutan sama-sama bekerja.
Kadang-kadang daerah pengamanan suatu pengaman sengaja dibuat overlap dengan daerah pengaman seksi berikutnya, dengan maksud untuk memberi pengaman cadangan pada seksi berikutnya. Jadi daerah sendiri pengaman ini bertugas sebagai pengaman utama, sedangkan di seksi berikutnya bertugas sebagai pengaman cadangan dan untuk mendapatkan selektivitas maka pengaman diberi penundaan waktu (time delay). Jadi selektivitas dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu:
1. Pembagian atas daerah-daerah pengaman 2. Koordinasi denganpeningkatan waktu (time grading).
6-4-3 Keandalan (reliability)
Dalam keadaan normal pengaman tidak bekerja selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun suatu pengaman tidak perlu bekerja, tetapi pengaman bila diperlukan harus dan pasti bekerja, sebab jika gagal bekerja dapat mengakibatkan kerusakan yang lebih parah pada peralatan yang diamankan, atau mengakibatkan bekerjanya pengaman lain, sehingga daerah itu mengalami pemadaman yang lebih luas (black out). Pengaman
Gambar 6-30. Daerah pengamanan gangguan
Saklar dan Pengaman
338
itu tidak boleh salah kerja (mistrip), sebab dapat mengakibatkan pemutusan-pemutusan yang tidak perlu dan pemadaman yang tidak semestinya.
Susunan alat-alat pengaman itu harus dapat diandalkan, baik pengaman itu sendiri maupun alat-alat lainnya serta hubungan-hubungannya. Keandalan pengaman tergantung kepada desain, pengerjaan (workman ship) dan perawatannya. Untuk beberapa pengaman tidak harus bekerja, tetapi harus pasti dapat bekerja bila sewaktu-waktu diperlukan. Oleh karena itu, pengujian secara periodik perlu sekali dilakukan khususnya rele+PMT. Hal ini dimaksudkan untuk:
1. Mengetahui apakah pengaman masih dapat bekerja sebagaimana mestinya
2. Mengetahui penyimpangan-penyimpangan karakteristik yang selanjutnya untuk mengadakan koreksi penyetelan
3. Membandingkan hasil-hasil pengujian sebelumnya, agar diketahui proses memburuknya rele pengaman alat bantunya sehingga dapat direncanakan perbaikan dan penggantinya.
Hasil pengujian periodik dan catatan bekerjanya rele sebagai akibat gangguan sangat bermanfaat untuk mengadakan evaluasi dan analisa pengaman pada sistem tenaga listrik.
6-4-4 Kecepatan bereaksi Makin cepat pengaman bekerja, tidak hanya dapat memperkecil
kerusakan akibat gangguan, tetapi juga dapat memperkecil kemungkinan meluasnya akibat-akibat yang timbul oleh gangguan. Oleh karena itu, pada umumnya dikehendaki waktu kerja pengaman yang secepat mungkin.
Ada kalanya demi untuk terciptanya selektivitas dikehendaki adanya penundaan waktu (time delay), tetapi secara keseluruhan tetap dikehendaki penundaan waktu itu secepat mungkin. Di samping itu, harus diteliti pula apakah penundaan waktu itu tidak membahayakan bagian yang terganggu dan peralatan yang dilalui gangguan. Jika membahayakan, maka harus dicari jenis pengaman yang lain yang dapat memberi selektivitas yang baik dengan waktu yang lebih cepat.
6-4-5 Pentanahan Tegangan Menengah Menurut fungsi pentanahan, sistem pentanahan dapat dibedakan
menjadi dua, yaitu (a) pentanahan sistem (pentanahan netral) dan (b) pentanahan umum (pentanahan peralatan). Pentanahan sistem berfungsi untuk: (1) peralatan/saluran dari bahaya kerusakan yang diakibatkan gangguan fasa ke tanah, (2) peralatan/saluran dari bahaya kerusakan yang diakibatkan tegangan lebih, (3) makhluk hidup terhadap tegangan langkah (step voltage), serta untuk kebutuhan proteksi jaringan. Sedangkan pentanahan umum berfungsi untuk melindungi: (1) makhluk hidup terhadap tegangan sentuh dan (2) peralatan dari tegangan lebih.
Dengan pentanahan tersebut diperoleh arus gangguan tanah yang besarnya bergantung pada impedansi pentanahan sedemikian rupa
Saklar dan Pengaman
339
sehingga alat-alat pengaman dapat bekerja selektif tetapi tidak merusak peralatan di titik gangguan.
Bagian yang diketanahkan adalah titik netral sisi TM trafo utama/gardu induk (pentanahan bertahanan) dan kawat netral sepanjang jaringan TM (pentanahan langsung). Ada tiga macam pentanahan pada JTM, yaitu a) Pentanahan netral dengan tahanan tinggi
Pentanahan dengan tahanan tinggi dimaksudkan untuk memperoleh hasil optimum dengan mengutamakan keselamatan umum sehingga lebih layak memasuki daerah perkotaan dengan SUTM. Untuk jaringan 3 fasa hubungan bintang dengan kawat tahanan pentanahan 500 Ohm (pola I) di pasang titik netral sisi TM trafo utama,
(6-11)
maka besar arus gangguan yang dijinkan adalah: Ikt = 25 ampere di mana: Xico = Reaktansi kapasitif urutan nol dari jaringan Ikt = Arus kawat tanah Terjadinya busur listrik masih tetap dapat dicegah. Karena besar arus tanah lebih sangat kecil maka kerusakan peralatan pada titik gangguan sangat berkurang (hampir tidak ada). Bila diinginkan pelayanan dapat dipertahankan sekalipun masih ada gangguan tanah menjadi keuntungan yang diperoleh pada sistem yang tidak ditanahkan. Tetapi pada umumnya pada sistem tegangan di atas 13,2 kV, operasi yang demikian tidak diperbolehkan, dengan demikian pengaman harus dilengkapi dengan rute arus tanah. b) Pentanahan netral dengan tahanan rendah
Pentanahan dengan tahanan rendah dimaksudkan untuk memperoleh hasil optimum dari kombinasi antara faktor ekonomi, keselamatan umum dan yang layak untuk mempergunakan SUTM bagi daerah luar kota maupun SKTM bagi daerah padat dalam kota. Sistem pentanahan dengan tahanan rendah digunakan untuk jaringan hubungan bintang fasa tiga kawat. Sistem pentanahan ini dapat mencegah terjadinya busur listrik yang menimbulkan tegangan lebih peralihan yang besar. Tahanan pentanahan di titik netral sisi TM trafo utama adalah 12 Ohm untuk SKTM, 40 Ohm untuk SUTM atau campuran SKTM dan SUTM.
Ik-t = (0,10 s/d 0,25) x I3 (6-12)
dengan ketentuan:
Ik-t < 1000 untuk RN= 12 Ohm Ik-t < 300 untuk RN = 40 Ohm I3 = arus gangguan tiga fasa
3XicoRN
Saklar dan Pengaman
340
Karena besar arus gangguan dibatasi, maka kerusakan peralatan pada titik gangguan dikurangi, sedangkan selektivitas dari rele arus lebih masih terjamin. Karena tagangan pada fasa-fasa sehat dibatasi di bawah tegangana jala-jala, dimungkinkan menggunakan peralatan dengan isolasi dasar yang dikurangi, demikian juga angka pengenal (rating) arester dapat dikurangi. c) Pentanahan netral dengan pentanahan langsung
Pentanahan secara langsung (tanpa tahanan) dimaksudkan untuk memperoleh hasil optimum dengan mengutamakan ekonomi sehingga denga SUTM layak dipakai di daerah luar kota sampai daerah terpencil. Untuk jaringan hubung bintang tiga fasa empat kawat (multi grounded) di pasang sepanjang jaringan. Biasanya tahanan elektroda dari bumi ke tanah di setiap titik pentanahan di batasi maksimum 5 Ohm, sedangkan arus gangguan ke tanah tidak dibatasi.
6-4-6 Hubungan Sistem Pentanahan dan Pola Arus Pengaman Lebih 6-4-6-1 Hubungan Sistem Pentanahan Tahanan Tinggi dan Pola Arus
Pengaman Lebih
Sistem pentanahan ini lebih kebal terhadap gangguan yang bersifat sementara. Mengingat kecilnya arus gangguan tanah (<25 A) pengamanan hanya dengan rele arus lebih normal tidak dapat digunakan lagi dan arus dilengkapi dengan relai gangguan tanah terarah yang lebih rumit dan mahal. Demikian pula selektivitas (diskriminasi) hanya dilakukan dengan waktu (khususnya gangguan fasa tanah).
Pengamanan PBO-2 (Penutup Balik Otomatis, Automatic Circuit Recloser) di sisi hilir tidak dapat dilakukan.
Saklar Seksi Otomatis (SSO) yang dapat dipergunakan pada sistem ini harus jenis pengindera tegangan dan koordinasinya dilakukan dengan penyetelan waktu, SSO dengan pengindera arus tidak dapat digunakan.
Alat pengaman fasa tunggal tidak dapat digunakan untuk mengamankan gangguan satu fasa ke tanah karena arus gangguannya kecil.
6-4-6-2 Hubungan Sistem Pentanahan Tahanan Rendah dan Pola Arus Pengaman Lebih
Arus gangguan fasa tanah pada sistem ini tidak terlalu besar (maksimum 1000 A untuk sistem SKTM dan 300A untuk SUTM) sehingga gangguan pada lingkungan akibat arus tanah (step voltage dan gangguan pada jaringan telekomunikasi) berkurang (dibatasi). Demikian pula penggunaan peralatan (PMT dan penghantar) dapat diplih yang lebih ringan dan ekonomis.
Mengingat adanya tahanan netral, maka arus gangguan tanah hasilnya kecil sehingga tidak efektif bagi penggunaan relai arus lebih dengan karakteristik waktu arus terbalik (invers), sebaliknya dapat dipergunakan relai dengan karakteristik waktu tetap yang lebih selektif dan mudah penyetelannya.
Saklar dan Pengaman
341
PBO yang dipakai harus dari relai dengan pengatur elektronik untuk mendapatkan karakteristik waktu tetap bagi gangguan fasa tanah. Demikian pula SSO perlu dilengkapi dengan pengindera arus fasa tanah yang rendah.
Alat pengaman fasa tunggal tidak dapat dipergunakan untuk mengamankan gangguan satu fasa tunggal karena arus kapasitif (terutama SKTM) perlu diperhitungkan.
6-4-6-3 Hubungan Sistem Pentanahan Langsung dan Pola Arus Pengaman Lebih
Dengan tidak adanya tahanan netral maka rus hubung tanah menjadi relatif sangat besar dan berbanding terbalik dengan letak gangguan tanah sehingga perlu dan dapat dipergunakan alat pengaman PMT + rele (berpengaman sendiri/LsP) yang dapat bekerja cepat dan dapat memanfaatkan alat pengindera dengan karakteristik waktu terbalik (invers-time) dengan sebaik-baiknya.
Karena gangguan arus fasa tanah besar, maka dapat dilakukan koordinasi antara PMT-relai arus lebih atau PBO dengan fuse atau antara PBO dengan SSO secara baik sekali.
Dengan didasarkannya sistem ini pada tiga fasa empat kawat, fasa-netral, maka peralatan pengaman fasa tunggal yang lebih selektif (PBO, SSO dan fuse dapat dimanfaatkan).
Karena arus gangguan fasa tanah besar dan kejadian gangguan fasa tanah relatif banyak dan PBO relatif sering bekerja, maka peralatan kemampuan (PMT, PBO dan lain-lain) harus disesuaikan dengan besarnya arus gangguan dan frekuensi buka tutup PBO (misalnya tidak menggunakan PMT berisi minyak minimum).
6-4-7 Sistem-Sistem yang Tidak Simetris Seperti diuraikan di atas, sistem-sistem ini pada dasarnya tidak
simetris karena mengandung bagian-bagian yang tidak simetris, misalnya saluran yang tidak di transposisi. Jadi sistem ini pada kerja normal tidak simetris. Besarnya arus lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain: a) Tegangan (volt).
Tegangan pada saat terjadi gangguan meningkat makin besar sehingga menyebabkan arus yang timbul makin besar pula.
b) Impedansi (ohm) Impedansi ini dipengaruhi oleh nilai impedansi trafo, impedansi saluran, impedansi titik gangguan dan jarak gangguan dari terminal sumber/trafo yang makin jauh menyebabkan impedansi saluran makin besar pula.
c) Jenis gangguan Jenis gangguan penyeyab timbulnya arus lebih mempengaruhi impedansi tiap alat dan saluran serta rangkaian ekuivalen sistem saat gangguan. Misalnya, arus gangguan atau arus lebih karena gangguan hubung singkat fasa-fasa lebih kecil dari arus gangguan tiga-fasa. Rangkaian
Saklar dan Pengaman
342
ekievalen sistem saat terjadinya gangguan sehingga mempengaruhi impedansi ekuivalen sistem saat terjadi gangguan.
d) Tahanan pentanahan Nilai tahanan pentanahan mempengaruhi impedansi sistem, semakin kecil tahanan pentanahan semakin besar arus lebih atau sebaliknya.
e) Saat mulai gangguan Jika gangguan mulai saat gelombang tegangan melampaui puncak, maka arus lebih mencapai maksimum.
f) Perbandingan X/R dan faktor daya Jika rasio X/R naik (besar dan faktor daya menurun) maka arus lebih asimetri akan naik dan sebaliknya.
6-4-8 Pengaman Terhadap Arus Lebih TM Arus lebih adalah arus yang timbul karena terjadinya gangguan/
hubungan singkat pada sistem/peralatan yang diamankan. Beban lebih adalah beban/arus yang melebihi nilai nominalnya, yang untuk waktu tertentu dapat ditolerir adanya untuk kepentingan pengusahaan, yang besar dan waktunya dibatasi oleh kemampuan alat/sistem JTM untuk menahannya. Arus lebih timbul disebabkan oleh hubungan singkat antara fasa dan atau antara fasa dengan tanah/netral. Hubungan singkat ini dapat terjadi karena terjadinya gangguan.
Pada SKTM, gangguan yang berasal dari dalam dapat disebabkan pemasangan yang kurang baik, penuaan, dan beban lebih. Sedangkan gangguan dari luar berupa misalnya gangguan-gangguan mekanis karena pekerjaan galian saluran lain, kendaraan-kendaraan yang melewati di atasnya, dan deformasi tanah. Gangguan pada SKTM umumnya bersifat permanen. Pada SUTM, sebagian besar gangguan disebabkan pengaruh dari luar yaitu angin dan pohon, kegagalan pengaman tegangan lebih/petir, kegagalan atau kerusakan peralatan dan saluran (misalnya peralatan yang dipasang kurang baik, kawat putus pada konektor/lepas, dan sebagainya), manusia, hujan dan cuaca, binatang atau benda-benda asing (misalnya benang layang-layang dari bahan non isolasi, ular dan sebagainya). kegagalan atau kerusakan peralatan dan saluran (misalnya peralatan yang dipasang kurang baik, kawat putus pada konektor/lepas, dan sebagainya), manusia, hujan dan cuaca, binatang atau benda-benda asing (misalnya benang layang-layang dari bahan non isolasi, ular dan sebagainya). Gangguan pada SUTM dapat dibagi dua, yaitu:
1. Gangguan sementara yang dapat hilang dengan sendirinya atau dengan memutuskan sementara bagian yang terganggu dari sumber tegangannya. Gangguan sementara jika tidak dapat hilang dengan segera, baik hilang dengan sendirinya maupun karena bekerjanya alat pengaman (PBO) dapat berubah menjadi gangguan permanen (tetap) dan menyebabkan pemutusan tetap.
2. Gangguan permanen (tetap) di mana untuk membebas kannya diperlukan tindakan perbaikan dan atau menyingkirkan penyebab gangguan tersebut
Saklar dan Pengaman
343
Gambar 6-31. SUTM dalamkeadaan gangguan satu kawat ke tanah
Gambar 6-32. SUTM dalam keadaan gangguan 2 kawat ke tanah
Menurut kejadiannya, penyebab timbulnya arus lebih dapat dibagi dua jenis, yaitu a) Gangguan shunt dan b) Gangguan seri. Kedua jenis gangguan ini menyebabkan sistem-sistem yang pada kerja normal simetris (seimbang) menjadi tidak simetris. Pada SUTM gangguan yang umum terjadi adalah gangguan shunt yang dapat berupa hubungan singkat satu kawat ke tanah, dua kawat ke tanah dan akhirnya yang paling jarang adalah hubungan tiga kawat ke tanah.
Gangguan seri, yang disebabkan oleh kawat putus atau fuse putus, ketidakseimbangan seri karena impedansi saluran tidak simetris dan karena penggunaan dua buah trafo fasa tunggal untuk mensuplai beban tiga fasa. Dalam hal ini dua fasa simetris terhadap fasa ketiga, yang terakhir ini sebenarnya termasuk sistem-sistem yang pada kerja normal tidak simetris tetapi karena sifatnya khusus, yaitu dua fasa simetris terhadap fasa ketiga maka pembahasannya dimasuk-kan di sini yang dimaksud dengan sistem-sistem yang pada kerja normal tidak simetris adalah sistem-sistem di mana terdapat bagian-bagian yang tidak simetris di mana impedansi-impedansi saluran atau beban pada tiga fasa tidak sama.
6-4-9 Hubungan Singkat Satu Kawat ke Tanah Penyebab hubungan singkat kawat ke tanah antara lain karena:
(1) Salah satu isolator pecah (dalam hal ini tahanan gangguan kecil) yang disebabkan benturan mekanis atau karena gelombang,
(2) Salah satu isolator pecah (dalam hal ini tahanan gangguan bisa besar sekali) tergantung dari kontak pohon/dahan dengan kawat dan kebasahan pohon itu sendiri.
Saklar dan Pengaman
344
6-4-8-1 Hubungan Singkat Dua Kawat ke Tanah Salah satu penyebab
hubungan singkat dua kawat ke tanah ialah bila pada salah satu fasa ada tegangan lebih yang tinggi, di samping isolator itu flash-over terjadi juga flash-over fasa di sisi lainnya ke isolator (back flash-over). Penyebab lain karena pohon/dahan mengenai dua fasa/kawat.
6-4-8-2 Hubungan Singkat Tiga Kawat ke Tanah
Sekalipun tipe gangguan ini jarang terjadi, patut juga mendapat perhatian dan pembahasan. Penyebabnya bisa antara lain petir yang menyambar tiga kawat fasa atau pohon.
Gangguan Seri
Gangguan yang umum terjadi pada jaringan tegangan menengah adalah:
a) Satu fasa terbuka karena satu kawat atau satu pelebur putus b) Dua fasa terbuka karena dua kawat atau dua pelebur putus c) Ketidak seimbangan pada impedansi saluran, dan ini biasanya
karena tidak ditransposisi d) Ketidak seimbangan pada impedansi saluran pada sistem dengan
jalan balik kawat netral.
6-4-8-3 Perhitungan Arus Hubung Singkat Perhitungan praktis untuk menghitung besar arus hubung singkat
dalam sistem distribusi tegangan menengah yang disuplai dari sistem tegangan tinggi (trafo tenaga) dapat dilakukan sebagai berikut. Data yang diperlukan:
a) MVAhs pada sisi busbar tegangan tinggi b) MVA, kV, XT % dari trafo tenaga yang mensuplai JTM c) JTM (penampang penghantar (q, mm2), panjang penghantar (l, km),
tahanan penghantar (RK, ohm) dan reaktansi induktif penghantar (XK , ohm).
Rumus menentukan arus hubung singkat:
tottoths
XRxUI
2233,
Gambar 6-33. SUTM dalam keadaan gangguan 3 kawat ke tanah
(a) Konstruksi (b) Rangkaian ekivalen
Saklar dan Pengaman
345
(6-14) (6-15) (6-16)
Untuk arus hubung singkat 1 fasa dipengaruhi oleh sistem pentanahan Menentukan impedansi total (Ztot). Impedansi sisi tegangan tinggi: kV
= tegangan sistem JTM (6-17) = 20 kV
Impedansi trafo tenaga: Impedansi sisi JTM: (6-18)
ZK = RK + jXK
6-5 Jenis Pengaman Jenis pengaman yang digunakan pada jaringan tegangan menengah
antara lain:
1. Pengaman lebur (Fuse Cut Out, FCO) 2. Relai Arus Lebih (Over Current Relay) 3. Relai Arus Gangguan Tanah (Ground Fault Relay) 4. Relai Arus Gangguan Tanah Berarah (Directional Ground Fault
Relay) 5. Relai Penutup Balik (Reclosing Relay) 6. Penutup Balik Otomatis (PBO, Automatic Circuit Recloser) 7. Saklar Seksi Otomatis (SSO, Sectionalizer).
6-5-1 Pengaman lebur Pengaman lebur (FCO) merupakan pengaman bagian dari saluran
dan peralatan dari gangguan hubung singkat antar fasa, dapat pula sebagai pengaman hubung singkat fasa ke tanah bagi sistem yang ditanahkan langsung. Berdasarkan bentuk fisik pelebur dibedakan menjadi:
Tertutup (enclosed) Terbuka (open) Elemen terbuka (open link)
Berdasarkan cara kerjanya dibedakan menjadi: Tipe expultion Tipe limiting
Karakteristik fuse cut out mempunyai sepasang garis lengkung yang disebut karakteristik arus waktu. Lengkung yang berada di bawah disebut waktu lebur minimum (minimum melting time), lengkung di atas disebut waktu bebas maksimum (maximum clearing time). Ada dua tipe fuse cut out
tottoths
XRxUI
2222,
nhs ZZZZ
xUI3
31,021
hsHV MVA
kVZ2
r
rHV MVA
kVXZ100
% 2
Saklar dan Pengaman
346
yaitu tipe cepat (K) dan tipe lambat (T). Perbedaan kedua tipe ini terletak pada speed ratio-nya.
6-5-2 Relai Arus Lebih Relai arus lebih merupakan pengaman utama sistem distribusi
tegangan menengah terhadap gangguan hubung singkat antar fasa. Relai arus lebih adalah suatu relai yang bekerja berdasarkan adanya kenaikan arus yang melebihi nilai setting-nya pengaman tertentu dalam waktu tertentu. Berdasarkan karakteristik waktu relai arus lebih dibagi menjadi 3, yaitu:
a) Tanpa penundaan waktu (instaneous) b) Dengan penundaan waktu c) Dengan penundaan waktu tertentu (definite time OCR) d) Dengan penundaan waktu berbanding terbalik (inverse time OCR) e) Kombinasi 1 dan 2
6-5-3 Relai Arus Gangguan Tanah Relai arus gangguan tanah (ground fault relay) merupakan
pengaman utama terhadap gangguan hubung singkat fasa ke tanah untuk sistem yang ditanahkan langsung atau melalui tahanan rendah.
6-5-4 Relai Arus Gangguan Tanah Berarah Relai arus gangguan tanah berarah (directional ground fault relay)
adalah pengaman utama terhadap hubung singkat fasa ke tanah untuk sistem yang ditanahkan melalui tahnan tinggi.
6-5-5 Relai Penutup Balik Relai penutup balik (reclosing relay) adalah pengaman pelengkap
untuk membebaskan gangguan yang bersifat temporer untuk keandalan sistem.
6-5-6 Penutup Balik Otomatis Penutup balik otomatis (PBO, automatic circuit recloser) digunakan
sebagai pelengkap untuk pengaman terhadap gangguan temporer dan membatasi luas daerah yang padam akibat gangguan.
PBO menurut media peredam busur apinya dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu:
a) Media minyak b) Vacum c) SF6
PBO menurut peralatan pengendalinya (control) dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:
a) PBO Hidraulik (kontrol hidraulik) b) PBO Terkontrol Elektrik
Urutan operasi PBO:
Saklar dan Pengaman
347
a) Pada saat terjadi gangguan, arus yang mengalir melalui PBO sangat besar sehingga menyebabkan kontak PBO terbuka (trip) dalam operasi cepat (fast trip)
b) Kontak PBO akan menutup kembali setelah melewati waktu reclose sesuai setting. Tujuan memberi selang waktu ini adalah untuk memberikan waktu pada penyebab gangguan agar hilang, terutama gangguan yang bersifat temporer
c) Jika gangguan bersifat permanen, PBO akan membuka dan menutup balik sesuai dengan settingnya dan akan lock-out (terkunci)
d) Setelah gangguan dihilangkan oleh petugas, baru PBO dapat dimasukkan ke sistem.
6-6 Saklar Seksi Otomatis Saklar seksi otomatis (SSO, Sectionalizer) adalah alat pemutus
untuk mengurangi luas daerah yang padam karena gangguan. Ada dua jenis SSO yaitu dengan pengindera arus yang disebut Automatic Sectionalizer dan pengindera tegangan yang disebut Automatic Vacum Switch (AVS). Agar SSO berfungsi dengan baik, harus dikoordinasikan dengan PBO (recloser) yang ada di sisi hulu. Apabila SSO tidak dikoordinasikan dengan PBO, SSO hanya akan berfungsi sebagai saklar biasa.
6-6-1 Pemilihan Pengaman Arus Lebih Pemilihan pengaman arus lebih untuk pengamanan sistem 20 kV disesuaikan dengan pola pengaman sistem SPLN 52-3:1983 berdasarkan sistem pentanahan netral
a) Sistem distribusi 20 kV tiga fasa, tiga kawat dengan pentanahan netral melalui tahanan tinggi (Pola I)
b) Sistem distribusi 20 kV tiga fasa, empat kawat dengan pentanahan langsung (Pola II)
c) Sistem distribusi 20 kV tiga fasa, tiga kawat dengan pentanahan netral melalui tahanan rendah (Pola III)
Pola I Pada gardu induk dipasang pengaman jaringan (pengaman utama)
yaitu pemutus beban dengan alat pengaman a) Relai arus lebih untuk membebaskan gangguan antar fasa b) Relai gangguan tanah terarah untuk membebaskan gangguan
tanah c) Relai penutup balik untuk memulihkan sistem dari gangguan
temporer dan untuk koordinasi kerja dengan peralatan di sisi hilir (SSO) atau AVS
d) Saklar seksi otomatis
Saklar dan Pengaman
348
e) Untuk mengisolasi daerah yang terkena sekecil mungkin gangguan. Alat ini mempunyai pengatur dan transformator tegangan sebagai penggerak dan pengindera.
f) Pelebur (PL) g) Dipasang pada titik percabangan antara saluran utama dan cabang.
Pola II Pengaman lebur dipakai sebagai pengaman saluran cabang
terhadap gangguan permanen
Pola III a) Pengaman utama dalam PMB yang dipasang di gardu induk yang
dilengkapi dengan Relai arus lebih untuk membebaskan gangguan antar fasa Relai gangguan tanah terarah untuk membebaskan gangguan
tanah Relai penutup balik untuk memulihkan sistem dari gangguan
temporer dan untuk koordinasi kerja dengan peralatan di sisi hilir SSO atau AVS
b) Saklar seksi otomatis (SSO) Untuk membatasi pemadaman sekecil mungkin maka jaringan utama
dapat dibagi dalam beberapa seksi dengan menggunakan SSO sebagai pemisah.
c) Pelebur (PL)
Sebagai pengaman terhadap gangguan permanen yang dipasang pada seluruh cabang.
6-6-2 Pemilihan Relai Arus Lebih Pemilihan relai arus lebih untuk pengamanan sistem 20 kV diatur
sebagai berikut. a) Sistem distribusi di mana variasi arus gangguannya cukup besar,
yaitu sistem distribusi yang disuplai dari sistem terpisah (PLTD), maka pemilihan relai arus lebih waktu tertentu akan lebih baik dari arus lebih waktu terbalik.
b) Sistem distribusi di mana variasi arus gangguannya kecil yang disuplai dari sistem yang sudah interkoneksi, maka pemilihan relai arus lebih waktu terbalik akan lebih baik dari arus lebih waktu tertentu.
c) Sistem distribusi yang disuplai lebih dari satu sistem pembangkit, untuk mendapatkan selektivitas dan untuk penyulang yang menginterkoneksikan relai arus lebih harus dilengkapi dengan relai tanah.
6-6-3 Pemilihan Relai Gangguan Tanah
Saklar dan Pengaman
349
Arus gangguan satu fasa sangat bergantung pada jenis pentanahannya. Pada umumnya gangguan satu fasa melampaui tahanan gangguan, sehingga menjadi semakin kecil. Oleh karena itu dipasang relai gangguan tanah secara khusus dan disesuaikan dengan sistem pentanahannya. Pemilihan relai gangguan tanah untuk pengamanan sistem 20 kV diatur sebagai berikut.
a) Untuk sistem pentanahan dengan tahanan tinggi, digunakan relai yang memiliki sensitivitas tinggi yaitu relai gangguan tanah berarah dengan karakteristik waktu tertentu.
b) Untuk sistem pentanahan dengan tahanan rendah di mana besarnya arus gangguan vs letak gangguan landai maka relai akan sukar dikkordinasikan dengan peningkatan arus, sehingga relai yang digunakan sebaiknya relai arus lebih karakteristik waktu tertentu. Demikian juga untuk gangguan tanah SKTM sistem Spindel (untuk panjang saluran 10 km)
c) Untuk sistem pentanahan langsung, besarnya arus hubung singkat vs letak gangguan sangat curam, sehingga relai yang digunakan adalah relai arus lebih dengan karakteristik waktu terbalik.
6-6-4 Koordinasi Pengaman
Untuk mendapatkan pengamanan yang selektif, maka penyetelan waktu relai pengaman arus lebih harus dibuat secara bertingkat.
tF > tset OCR di A > tset OCR di B (6-19) Untuk gangguan yang terjadi di titik F, relai A dan relai B akan pick-up karena tA > tB maka relai B akan bekerja lebih dahulu. Beda waktu dari kedua relai t = 0,4 detik. 6-6-5 Koordinasi Pengaman pada Jaringan Radial Misalkan gangguan terjadi pada sebuah jaringan radial seksi 2A (lihat gambar 6-35).
Untuk gangguan di seksi 2A, koordinasi pengaman sebagai berikut. a) Relai di GI bekerja dan memerintahkan PMT trip. b) Karena tidak ada tegangan, maka AVS-A1, AVS-A2, dan AVS-A3
membuka setelah selang waktu t3. c) Setelah tercapainya waktu penutup balik pertama PMT A masuk
kembali, kemudian selang waktu t1, AVS-A1 mendeteksi tegangan sehingga menutup.
Gambar 6-34 Penempatan Rele Pengaman pada Jaringan Radial
Saklar dan Pengaman
350
d) Karena di seksi 2A masih ada gangguan, maka PMT di A ditripkan lagi oleh relai pengaman (bila gangguan temporer, dengan masuknya AVS-1 sistem akan kembali normal)
e) Karena AVS-1 bertegangan sesaat (kurang dari t2) maka a langsung mengunci (lock out)
f) Setelah waktu recloser ke-2 tercapai, PMT masuk dan seksi A bertegangan
g) Seksi 2A, 3A dan 4A padam. h) Lampu indikator AVS-A1 menyala hijau, sedangkan AVS-A2 dan
AVS-A3 padam. 1A 2A 3A 4A RECLOUSER PCT OCR DGFR
T1 = Waktu mulai ada tegangan sampai dengan arus masuk (15 detik) T2 = Waktu untuk menentukan buka atau terkunci(5 detik) T3 = Waktu tanda mulai saat tegangan hilang sampai arus terbuka (18 detik)
6-6-6 Koordinasi Pengaman pada Jaringan Loop
Misalkan gangguan terjadi pada seksi 2A dari jaringan loop (lihat gambar 6-36.
Untuk gangguan di seksi 2A, koordinasi pengaman sebagai berikut.
a) Relai PMT-A bekerja, memerintahkan PMT-A trip b) Relai PMT-A bekerja, memerintahkan PMT-A trip c) Relai PMT-A bekerja, memerintahkan PMT-A trip d) Karena tidak ada tegangan pada penyulang A, maka AVS-A1 dan
AVS-A2 membuka setelah selang waktu t3. e) Setelah waktu recloser ke-1 dari penutup balik dicapai, maka PMT-A
masuk setelah selang waktu t1 dan AVS-A1 masuk. f) Karena gangguan di seksi 2A masih ada (permanen) maka PMT-A
trip lagi g) AVS-A1 langsung mengunci karena waktu merasakan tegangan
lebih kecil dari t2. h) Setelah waktu menutup balik ke-2 dari penutup balik tercapai PMT-A
masuk dan seksi 1A bertegangan.
Gambar 6-35 Koordinasi Pengaman pada Jaringan Radial
T = Control Device (kotak pengatur) PCT = Power Control Transformer
PMT AVS-A1 AVS-A2 AVS-A3
T T T
Saklar dan Pengaman
351
i) Setelah selang waktu t5 dari AVS-L, AVS-L akan masuk sehingga PMT-B trip karena relai di B merasakan adanya gangguan.
j) Pada penyulang B terjadi buka tutup, sampai AVS-A2 lock-out sehingga seksi 2A terisolasi dan seksi 3A mendapat suplai dari penyulang B.
GI 1A 2A 3A AVS-L PMT B AVS-B1 AVS-B2 1B 2B 3B
6-7 Penutup Balik Otomatis (PBO) Dalam pola II, penggunaan PBO, SSO dan FCO (pengaman lebur)
dapat dikoordinasikan. Pola ini digunakan dalam sistem jaringan 4 kawat dengan pentanahan multi grounded.
Keterangan: T1 = waktu mulai kotak pengatur bertegangan sampai AVS masuk kembali (5-
10 detik) T2 = waktu yang distel agar AVS terkunci, bila waktu merasakan tegangan
lebih kecil dari setting t2 T3 = waktu mulai kotak pengatur tidak bertegangan sampai AVS masuk
kembali (0,5-2 detik) T 5 = waktu mulai kotak pengatur tidak merasakan tegangan dari salah satu sisinya sampai AVS-L masuk secara otomatis t5 > tr +(n+1) t1 tr = waktu penutup balik n = banyaknya AVS
Gambar 6-37 Koordinasi PBO, SSO dan FCO
Gambar 6-36 Koordinasi Pengaman pada Jaringan Loop
PMT AVS-A1 AVS-A2
T T
T T
Saklar dan Pengaman
352
a) Koordinasi antara OCR/GFR dengan PBO
Secara fisik PBO ini semacam PMB yang mempunyai kemampuan sebagai pemutus arus hubung singkat yang dilengkapi dengan alat pengindera arus gangguan dan peralatan pengatur kerja membuka dan menutup serta mengunci bila terjadi gangguan permanen.
Untuk melakukan koordinasi antara OCR/GFR di gardu induk dengan PBO harus dibuat sedemikian rupa sehingga setiap terjadi gangguan setelah PBO, relai OCR/GFR tidak boleh trip sebelum PBO terkunci (lock out).
Oleh karena itu, harus dihitung terlebih dahulu waktu reset dan putaran dari relai OCR/GFR, agar supaya PMT tidak trip. Sebelum PBO terkunci total putaran relai OCR/GFR diusahakan kurang dari 100% pada saat PBO terkunci.
b) Koordinasi antara PBO dengan PBO Koordinasi antara PBO dengan PBO dapat dicapai dengan:
Memilih nilai arus trip minimum yang berbeda antara kedua PBO (yang menggunakan kontrol elektronik)
Mengatur pemakaian urutan operasi yang terbalik dari masing-masing PBO dengan cara mempelajari dan memilih karakteristik kerja dari kurva arus waktu. Faktor yang penting dalam koordinasi antara kedua bentuk kurva
arus waktu dari kedua PBO adalah perbedaan waktu antara kedua kurva untuk satu nilai arus tertentu (arus hubung singkat)
Perbedaan waktu minimum antara kedua kurva adalah untuk mengamankan agar kedua PBO tidak beroperasi secarav bersamaan.
c) Koordinasi antara PBO dengan SSO Bila terjadi gangguan di sisi hilir dari SSO maka PBO akan bekerja
membuka tutup dengan cepat pertama sampai kedua untuk menghilangkan gangguan yang bersifat temporer. SSO mengindera arus gangguan dan menghitung banyaknya buka tutup dari PBO, bila gangguan bersifat permanen, maka sesuai dengan penyetelan hitungan (count to open) SSO. SSO membuka pada saat PBO membuka sebelum buka tutup terakhir dan mengunci dari PBO.
d) Koordinasi antara PBO dengan PL PBO harus dapat mendeteksi arus gangguan di daerah pengaman
PL koordinasi maksimum antara PBO dan PL dapat dicapai dengan mengatur urutan kerja PBO dua, cepat atau lambat.
Saklar dan Pengaman
353
Operasi cepat pertama dan kedua untuk menghilangkan gangguan temporer sebelum operasi ketiga, yaitu operasi lambat pertama yang memberikan kesempatan pada PL untuk melebur (putus) lebih dahulu sehingga gangguan dapat diisolasi.
6-7-1 Kegagalan Pengaman
Seperti telah diuraikan di depan, untuk mendapatkan pengaman yang baik, maka kurva arus waktu ketahanan trafo/penghantar harus berada di atas kurva arus waktu pengamannya (atau jarak terdekat sekitar 25%) jika tidak maka akan terjadi kegagalan pengaman.
Penyebab berikutnya ialah kurva ketahanan trafo/penghantar tidak sesuai standar atau dengan data yang diberikan oleh pabrik. Jadi perlu pemutakiran data untuk koordinadi antara kurva arus waktu trafo dengan pengaman untuk menentukan pasangan pengamannya.
Penyebab lainnya ialah kurva pemutusan (trip) arus-waktu pengaman tidak sesuai dengan data yang diberikan pabrik sehingga perlu
Gambar 6-38. Penempatan PMT, PBO, PL dan SSO pada pangkal saluran cabang jaringan TM
Saklar dan Pengaman
354
dilakukan pengujian ulang. Jika terjadi kegagalan pengamanan, maka kemungkinan yang akan terjadi antara lain perubahan kurva arus-waktu pengaman relai, pelebur, PMT terlalu banyak beroperasi /umur tua , kotor atau rusak. Jika kotor dapat dibersihkan, tetapi jika terlalu tua atau rusak harus segera diganti.
6-7-2 Pengaman Terhadap Tegangan Lebih
Dalam keadaan operasi, suatu sistem tenaga sering mengalami gangguan yang dapat mengakibatkan teputusnya pelayanan daya ke pelanggan. Gangguan tersebut lebih sering terjadi pada jaringan distribusi. Terjadinya gangguan disebabkan oleh peningkatan tegangan pada hantaran
Contoh penempatan PMT, PBO, PL dan SSO pada pangkal saluran cabang jaringan TM dapat dilihat pada Gambar 6-38. Sedangkan penempatan PMT dan PL pada jaringan Spindel SKTM dapat dilihat pada Gambar 6-39.
Gambar 6-39 Penempatan PMT dan PL pada jaringan Spindel SKTM (PMT tanpa PBO) Pola 2
Contoh penempatan pengaman arus lebih pada jaringan TM
Saklar dan Pengaman
355
distribusi, yang dikenal dengan tegangan lebih, yang besar tegangan itu melampaui tingkat ketahanan isolasi dari hantaran distribusi. Dengan demikian terjadi hubung singkat antar kawat-kawat fasa ke tanah yang dapat menyebabkan PMT membuka.
Tegangan lebih ini antara lain ditimbulkan oleh:
a. Sambaran petir pada hantaran distribusi, baik merupakan sambaran langsung atau tidak langsung.
b. Surja hubung Oleh sebab itu, kebutuhan tingkat ketahanan isolasi dari suatu sistem
tenaga ditentukan oleh tegangan lebih akibat sambaran petir (tegangan lebih atmosfir) dan tegangan lebih akibat transien pada waktu switching.
a) Tegangan Lebih Atmosfir Tegangan lebih ini muncul pada JTM karena sambaran petir baik
langsung (jarang terjadi) maupun sambaran tidak langsung (sering terjadi), misalnya petir menyambar pohon atau benda lain yang lebih tinggi dari JTM lain menginduksi ke JTM yang berada di sekitar lokasi sambaran petir. Tegangan lebih atmosfir ini berkisar 345 kV.
Gambar 6-40. Penempatan PMT, PBO, PL , SSO
Saklar dan Pengaman
356
b) Tegangan Lebih Hubung Kondisi dalam jaringan listrik dibedakan menjadi dua, yaitu keadaan
stasioner (misalnya keadaan masa kerja suatu jaringan) dan keadaan sementara atau proses menuju keseimbangan (transien), yang timbul pada waktu switching atau memutus arus. Proses transien adalah
PTS 110
Gambar 6-41. Penempatan PMT, SSO, ST, FCO pada SUTM
Saklar dan Pengaman
357
peralihan dari kondisi stasioner I ke kondisi stasioner II yang hampir selalu menyebabkan osilasi tegangan dan arus, dan oleh karena itu menimbulkan peningkatan tegangan.
Karena adanya tahanan dalam jaringan, maka tegangan lebih diredam dan sesudah beberapa waktu tertentu tegangan itu menghilang. Dalam Gambar 6-41 digambarkan kondisi stasioner I dan II. Pada kondisi I, generator memberikan daya melalui suatu penghantar, transformator diteruskan ke pemakai. Fenomena itu tidak hanya merupakan penghantaran daya dari pembangkit ke pemakai melalui penghantar, melainkan dalam distribusi daya itu juga terdapat medan magnet yang mengelilingi penghantar-penghantar dan medan listrik antara penghantar-penghantar sendiri dan antara penghantar-penghantar dengan tanah. Medan magnet dan medan listrik itu mengandung energi berpulsa sebesar harga rata-rata frekuensi jaringan. Selama kondisi stasioner I energi dari pembangkit itu disimpan pada transformator, penghantar dan pemakai.
Saklar dan Pengaman
358
Sesudah membuka sakelar S (keadaan II) generator itu tidak menyerahkan daya lagi kepada pemakai, tetapi generator tetap memeberi energi medan listrik pada penghantar, walaupun energi itu hanya sedikit. Proses keseimbangan itu membawa keadaan energi antara kondisi stasioner yang masing-masing mempunyai muatan-muatan energi yang berbeda.
Gambar 6-43 Sambaran petir pada SUTM
Gambar 6-44. Kondisi I dan II dari Jaringan Distribusi
Saklar dan Pengaman
359
c) Karakteristik Tegangan Lebih
Teori tentang petir yang telah diterima secara luas bahwa awan dari daerah bermuatan positif dan negatif. Pusat-pusat muatan ini menginduksikan muatan memiliki polaritas berlawanan ke awan yang terdekat atau ke bumi. Gradien potensi awan di udara dntara pusat-pusat muatan di awan atau antara awan dan bumi tidak seragam, tetapi gradien tersebar timbul pada bagian konsentrasi muatan tertinggi. Konsentrasi muatan tertinggi dan gradien tegangan tertinggi dari awan ke bumi menimbulkan pelepasan muatan pada awan. Ketika gradien mencapai batas untuk udara-udara di daerah konsentrasi tekanan tinggi mengionisasi atau tembus (break down).
Muatan dari pusat muatan mengalir ke dalam kanal terionisasi, mempertahankan gradien tegangan tinggi pada ujung kanal dan melanjutkan proses tembus listrik. Formasi suatu sambaran petir berikutnya adalam tembus listrik progresif pada jalur busur api lebih kecil dari pada tembus listrik sesaat dan terintegrasi di udara sepanjang kanal.
Sambaran petir ke bumi diawali ketika muatan sepanjang tepi awan
menginduksikan suatu muatan lawan ke bumi (gambar 7-48), lidah arah bawah menyebar dari awan ke arah bumi seperti pada gambar 7-49. Jika pusat muatan kecil, semua muatan bisa saja dilepaskan selama lidah utama (pilot leader) terbentuk dan sambaran tidak lengkap.
Ketika sambaran lengkap, pusat muatan kecil tampaknya dikosongkan, akibatnya lidah petir juga berhenti. Begitu pusat muatan baru terbentuk maka lidah petir terbentuk lagi secara cepat.
+ + + + + + + + + + ++ + + ++++++++
Gambar 6-45. Muatan sepanjang tepi awan menginduksikan muatan lawan pada bumi
Saklar dan Pengaman
360
Begitu lidah petir mendekati bumi, sambaran ke arah atas terbentuk dan biasanya berawal dari titik tertinggi di sekitarnya. Bila lidah petir ke arah atas dan ke bawah bertemu (Gambar 6-47) suatu hubungan awan ke bumi terbentuk dan energi muatan dari awan dilepaskan ke dalam tanah. Muatan-muatan dapat terinduksi ke jaringan listrik yang berada di sekitar sambaran petir ke tanah. Walaupun muatan awan dan bumi dinetralisir melalui jalur awan ke tanah, muatan dapat terjebak pada jaringan listrik (Gambar 6-48).
Gambar 6-46. Lidah petir menjalar ke arah bumi
Gambar 6-47 Kilat sambaran balik dari bumi ke awan
Gambar 6-48 Kumpulan
Saklar dan Pengaman
361
Besar muatan yang terjebak ini tergantung pada gradien mula awan ke bumi dan kedekatan sambaran ke jaringan. Tegangan terinduksi pada jaringan listrik dari sambaran di tempat jauh, akan menjalar sepanjang jaringan dalam bentuk gelombang berjalan sampai dihilangkan oleh pengurangan (attenuasi), kebocoran, isolator rusak/pecah atau arester beroperasi bila sambaran langsung ke jaringan listrik dan tegangan meningkat secara cepat pada titik kontak. Tegangan ini juga menjalar dalam bentuk gelombang berjalan dalam dua arah dari titik sambaran, berusaha menaikkan tegangan potensial jaringan terhadap tegangan lidah petir arah ke bawah. Tegangan ini melampaui ketahanan tegangan jaringan terhadap tanah dari isolasi sistem dan jika tidak cukup dilengkapi dengan pengaman tegangan lebih, dapat berakibat pada kerusakan (kegagalan) isolasi.
Operasi arester akan membentuk suatu jalur dari kawat jaringan ke tanah untuk sambaran petir. Hal ini menyempurnakan mata rantai antara awan dan bumi untuk melepas energi awan dalam bentuk arus surja. Karena titik hubung jaringan ke tanah makin jauh dari titik kontak sambaran, maka sebagian kawat jaringan dapat membentuk suatu bagian dari jalur arus petir. Arester surja mempunyai karakteristik tembus listrik terkontrol yaitu pengaliran arus surja ke bumi melalui arester akan terhenti ketika tegangan benar-benar di bawah kawat tahanan isolasi sistem. Keadaan ini menyebabkan keberadaan arester surja begitu penting sebagai bagian dari sistem distribusi.
Menurut karakteristiknya, tegangan yang dihasilkan oleh sambaran petir akan meningkat mencapai nilai puncak secara cepat dan kemudian menurun menuju nol pada laju yang sangat lambat. Waktu yang diperlukan tegangan mencapai puncak biasanya dalam beberapa mikro detik atau kurang. Waktu ekor gelombang dapat mencapai 10 atau ratusan mikro detik, tegangan pada penghantar jaringan distribusi tang tersambar petir tidak seragam terjadi induksi muatan. Ketika lidah ini mendekati penghantar pada kecepatan 0,3048 m/mikro detik terjadi kenaikan tegangan induksi.
Bila sambaran petir mencapai penghantar, kenaikan tegangan menjadi lebih cepat karena arester yang biasanya dipakai pada jaringan distribusi mempunyai tegangan pengenal yang rendah, maka bisa saja arester beroperasi pada tegangan terinduksi tersebut. Perbandingan kenaikan tegangan terhadap waktu beroperasinya arester akan lebih rendah pada JTM dan JTT. Untuk mengetahui ketahanan tegangan isolasi terhadap tegangan petir dilakukan uji tegangan impuls di laboratorium.
Bentuk gelombang tegangan impuls ini distandarisasi (SPLN) sebesar 1,2 x 50 mikro detik, seperti terlihat pada gambar 6-49. Bentuk gelombang dan besar arus sambaran petir juga bervariasi. Hal ini juga telah distandarisasi untuk gelombang arus uji yaitu meningkat dari nol hingga mencapai nilai puncak dalam 8 mikro detik dan menurun mencapai nilai ½ puncak dalam 20 mikro detik sejak awal.
6-7-3 Karakteristik Tegangan Surja Ketika suatu saklar dalam rangkaian listrik dibuka atau ditutup akan
terjadi suatu transien hubung. Hal serupa juga akan terjadi pada JTM atau
Saklar dan Pengaman
362
JTT. Kombinasi dari resistansi, induktansi dan kapasitansi pada JTM sedemikian rupa sehingga tegangan lebih surja hubung yang dapat merusak
isolasi sistem tidak terjadi. Tetapi tegangan lebih surja hubung dapat terjadi akibat pukulan balik ketika proses membuka atau menutup saklar bangku kapasitor untuk perbaikan faktor daya. Pukulan balik yang terjadi saat membuka atau menutup saklar kapasitor menunjukkan suatu pemakaian yang tidak sempurna dari saklar. Penyelesaian terbaik dari masalah ini adalah mendapatkan saklar bebas pukulan balik dan mencegah tegangan lebih, daripada mencoba mengamankan atau memproteksinya.
Ferro resonansi juga dapat menghasilkan tegangan lebih merusak pada JTM. Tegangan lebih ini tidak benar-benar transien, karena bersiklus dan tetap ada dalam periode panjang. Tegangan lebih dapat terjadi ketika kapasitansi dirangkai secara seri dengan kumparan primer trafo tanpa beban atau berbeban rendah. Hal ini biasanya terjadi ketika proses hubung (switching) sebagai akibat dari suatu pelebur putus atau suatu penghantar JTM putus. Penyelesaian dari masalah ini adalah mengubah hubungan jaringan atau merevisi operasi saklar sehingga tegangan lebih tidak dapat terjadi. Cara ini dapat mengamankan isolasi dari tegangan lebih surja hubung.
6-7-4 Pengamanan Terhadap Tegangan Lebih Pengaman saluran distribusi menurut metode yang lama adalah
merupakan pengembangan dari metode yang digunakan pada saluran transmisi. Terdapat beberapa metode pengaman yang digunakan pada metode lama, antara lain kawat tanah, kawat netral dan sela batang.
a) Kawat Tanah (Overhead Statics) Metode pertama yang digunakan untuk pengaman saluran distribusi
adalah kawat tanah. Metode ini biasanya digunakan pada saluran transmisi, yang memerlukan ketahanan impuls isolasi sangat tinggi. Pada jaringan distribusi hal ini tidak mungkin dipenuhi, khususnya pada tempat-tempat peralatan seperti pada transformator atau gardu distribusi. Kriteria utama perencanaan dalam mengevaluasi kawat tanah adalah persoalan back-over ke tanah. Penggunaan kawat tanah memerlukan tahanan pentanahan yang
Gambar 6-49 Gelombang tegangan uji impuls 1,2 x 50 mikro detik
Saklar dan Pengaman
363
sangat rendah untuk setiap struktur dan ketahanan impuls isolasi yang tinggi. Pada sistem multi grounded Y, kawat netral dihubungkan pada titik dengan tanah, yang selanjutnya mempengaruhi arus petir pada seluruh peralatan pada saluran. Ketika arus petir yang besar terjadi dan mengenai transformator dan peralatannya, hasil kerja kawat btanah ini tidak signifikan dalam mengamankan saluran dan flash over.
b) Kawat Netral Kawat netral ditempatkan di ataw kawat penghantar fasa
menggantikan kedudukan kawat tanah, tetapi persoalan yang sama menyangkut back flash over tetap saja terjadi. Hasil riset yang telah dilakukan di Australia menunjukkan bahwa baik kawat tanah (di atas kawat fasa) maupun kawat netral (di bawah kawat fasa), keduanya meredam sedikit gelombang surja. Kawat netral di atas kawat fasa, ternyata tidak ekonomis atau tidak merupakan metode yang baik untuk melindungi peralatan terhadap sambaran petir.
c) Sela Batang Latar belakang dari metode pengamanan terhadap tegangan lebih
menggunakan sela batang adalah apabila saluran harus flash over, maka dibuat ketahanan impuls dari saluran tinggi dan dibuat pada beberapa titik dari saluran ketahanan impuls isolasi yang lebih rendah, sehingga flash over akan terjadi pada ketahanan impuls isolasi yang lebih rendah tersebut, yaitu melalui sela batang. Untuk hal ini memerlukan beroperasinya pemutus daya (circuit breaker) untuk menghilangkan gangguan 50 Hz tersebut. Dengan adanya PBO berkecepatan tinggi, jenis pengaman ini agak banyak digunakan pada beberapa wilayah di dunia misalnya di Inggris. Ada satu persoalan yang timbul dengan penggunaan metode sela batang ini, yaitu mengontrol jarak sela (gap) karena hal ini sangat menentukan flash over. Jika arus gangguan sangat besar, maka bunga api pada sela batang dapat merusak peralatan di sekitarnya.
6-7-5 Pengamanan Saluran Distribusi Masa Kini Pada akhir tahun 1960-an telah diadakan studi antara para
industriawan IEEE dan General Electric Company. Studi tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan Scale-model yang dikenal sebagai teknik model Nanosecond dan pendekatan Monte Carlo untuk menentukan parameter- parameter dari sambaran petir. Studi ini menggunakan model skala dari beberapa tipe struktur saluran distribusi untuk menentukan metodologi dari pengaman petir.
Dalam studi tersebut diamati berbagai metode pengaman petir, mencakup penggunaan lighning arrester (LA) pada seluruh fasa, arrester-arrester pada ujung-ujung tiang (dead ends), kawat tanah dan proteksi yang hanya pada fasa tengah dari saluran tiga fasa.
Hasil utama dari riset tersebut menunjukkan bahwa dengan menggunakan lightning arrester pada seluruh fasa pada interval tertentu, ternyata lebih baik dari pada menggunakan kawat tanah atau dengan
Saklar dan Pengaman
364
menggunakan pengaman hanya pada fasa teratas. Arrester dipasang sedekat mungkin dengan trafo. Penempatan arrester pengaman trafo pada gardu induk di sisi 20 kV yang ditanahkan tidak efektif (kawat netral ditanahkan dengan tahanan). Jarak arrester dengan trafo maksimum 6 mm (SPLN 7-1978). Jenis arrester yang biasa dipakai adalah jenis katub (valve arrester) dan jenis tabung ledak (expulsion).
Jenis arrester tabung ledak ini mempunyai pengaman yang lebih baik, khususnya pada saluran yang mempunyai tingkat gangguan yang rendah. Alat ini baik digunakan pada saluran di pedesaan yang dilayani oleh gardu yang kecil. Persoalan yang timbul adalah pada setiap terjadi spark-over terjadi perubahan pada tabung sehingga memberikan nilai yang berubah-ubah pada tingkat spark-over. Sesudah 5 dan 6 kali alat ini beroperasi, ketahanan impuls isolasi dari lightning arrester ini dengan mudah menjadi tinggi dari ketahanan impuls isolasi peralatan yang diamankan. Dengan demikian LA tidak dapat lagi memberikan pengamanan yang memadai.
Spesifikasi LA yang dipakai untuk JTM 20 kV adalah (a) 18 kV, 5 kA pada sisi 20 kV trafo distribusi hubungan bintang diketanahkan, (b) 24 kV, 5 kA Seri A pada sisi 20 kV trafo distribusi hubungan delta, maupun (c) fasa satu dari sistem delta 24 kV, 10 kA untuk jaringan pada sisi 20 kV trafo daya pada gardu induk.
Gambar 6-50. Skema Sambaran Petir yang Dialihkan Arrester ke Tanah
Saklar dan Pengaman
365
6-7-6 Arrester pada Transformator Distribusi Terminal pentanahan arrester diinterkoneksikan dengan terminal
pentanahan tangki trafo dan terminal pentanahan netral trafo (netral diketanahkan langsung). Jika ditanahkan bersama maka arus surja yang mengalir ke tanah melalui suatu impedansi (Z) menyebabkan jatuh tegangan (drop voltage) pada impedansi tersebut hingga tegangan tinggi pada kumparan primer. Karena kumparan sekunder dan tangki mempunyai
Gambar 6-51 Pengamanan dengan arrester tanpa interkoneksi terminal pentanahan
Saklar dan Pengaman
366
Jika interkoneksi (solid) antara tangki dan titik pentanahan bersama tidak dimungkinkan, dapat digunakan celah antara titik pentanahan dan netral kumparan sekunder (Gambar 6-53).
Hal ini menyebabkan arus surja dilewatkan melalui beberapa impedansi pentanahan paralel dan bahaya terhadap kerusakan isolasi diminimalkan, meskipun dalam kondisi arus surja besar dan impedansi pentanahan tinggi.
Gambar 6-54 Hubungan arrester pada sistem bintang yang diketanahkan
Gambar 6-52. Pengamanandengan arrester dan interkoneksi ke terminal pentanahan (solid)
Gambar 6-53. Pengamanan dengan arrester dan interkoneksi pentanahan melalui celah (gap)
beda potensial terhadap tanah, maka timbul beda potensial di antara kedua kumparan, dan di antara kumparan primer dengan tangki (Gambar 6-51). Jika ditanahkan bersama maka akan menurunkan drop tegangan pada impedansi tersebut di atas, yaitu menghilangkan beda poten sial yang dihasilkan oleh drop tegangan pada impedansi tanah (Gambar 6-52).
Saklar dan Pengaman
367
6-7-7 Arrester pada Recloser (PBO)
Arrester dipasang sedekat mungkin ke PBO di kedua sisi (sisi primer dan beban) pada tiap penghantar fasa dan pertimbangan lain seperti pada trafo. Jika dari segi ekonomis arrester dipasang hanya pada satu sisi, maka arrester sebaiknya dipasang pada sisi sumber PBO.
Surja petir pada sisi sumber dapat menyebabkan flash over pada bushing sisi sumber dan mengakibatkan gangguan fasa ke tanah, dan harus diamankan oleh PBO cadangan.
Suatu arrester pada sisi sumber akan mengamankan surja di sisinya sendiri yang mengamankan arus ikutan frekuensi daya (50 Hz). Jika bushing sisi beban dikenali petir dari sisi beban, maka PBO berfungsi secara normal untuk menginterupsi dan mengamankan arus ikutan frekuensi daya 50 Hz. Bila PBO dipakai pada GI, arrester mengamankan sisi sumber pada tiap fasa, karenanya pada sisi beban tiap fasa memerlukan satu arrester.
6-7-8 Arrester pada Kapasitor Distribusi Penggunaan arrester pada kapasitor distribusi mempertimbangan
faktor-faktor yang sama dengan pada PBO, yaitu faktor jarak yang terdekat dengan bangku kapasitor dan interkoneksi pentanahan seperti pada trafo.
a) Arrester dipasang pada tiang kawat penghantar, baik pada trafo tiga fasa maupun satu fasa untuk sistem bintang (Y) (lihat Gambar 6-54).
b) Pemakaian arrester pada sistem delta (tidak ditanahkan), tegangan arrester adalah tegangan line to line (Gambar 6-58).
Gambar 6-55. Pemakaian arrester pada sistem delta
Saklar dan Pengaman
368
Arrester surja direkomendasikan untuk semua instalasi kapasitor, mencakup bangku kapasitor hubungan delta, bangku kapasitor hubungan bintang dengan netral diketanahkan bercelah, bangku kapasitor hubungan bintang netral tidak diketanahkan dan bangku saklar. Arrester juga direkomendasikan untuk semua hubungan bintang netral ditanahkan secara solid (batang) bangku kapasitor tiga fasa dengan kapasitas 500 kVAr atau lebih kecil. Untuk kapasitas di atas 500 kVAr, bangku kapasitor tanpa saklar pengatur daya, harus dipelajari secara tersendiri dalam menentukan
kebutuhan pengaman dengan arrester. Untuk bangku kapasitor besar
yang diketanahkan dengan batang padat (tanpa tahanan), tanpa saklar pengatur daya, tidak mudah surja petir memberikan tegangan berbahaya pada bangku kapasitor.
Arrester harus dipasang pada sisi sumber saklar kapasitor dari semua bangku kapasitor yang mempunyai saklar pengatur faktor daya.
Penempatan ini umum dan praktis, dan secara empirik diperlukan untuk mengatasi kemungkinan timbulnya tegangan lebih dari pukulan balik saklar.
6-7-9 Arrester pada Pengaman Lebur Arrester yang dipasang pada sisi
primer pengaman lebur (PL) dimaksudkan agar ketika terjadi surja petir, arus surja
petir mengalir ke arrester diteruskan ke tanah, tidak melalui PL, sehingga PL tidak putus (lebur) (lihat Gambar 6-56). 6-7-10 Arrester pada SUTM
Penempatan arrester pada SUTM dilaksanakan sebagai berikut. Arrester sedapat mungkin dipasang pada titik percabangan dan pada ujung-ujung saluran yang panjang, baik saluran utama maupun saluran cabang.
Jarak antara arrester yang satu dengan yang lain tidak boleh melebihi 1000 meter dan di daerah yang berpotensi banyak petir berjarak tidak boleh melebihi 500 meter. Jika terdapat kabel tanah sebagai bagian dari sistem, arrester sebaiknya dipasang pada ujung kabel dan dipasang pada tiap kawat fasa.
6-7-11 Arrester pada SKTM Saluran kabel tegangan menengah bawah tanah tahan terhadap gangguan petir. Saluran kabel bawah tanah mulai dari generator sampai pelanggan. Jika SKTM digabung dengan SUTM, maka petir dapat masuk ke SKTM melalui SUTM pada tiang naik. Jadi arrester harus dipasang pada tiang naik dan pada tiap kawat penghantar fasa.
Gambar 6-56. Hubungan arrester yang direkomen-dasikan untuk sisi beban di bagian primer pelebur (PL)
Saklar dan Pengaman
369
6-7-12 Kegagalan Pengamanan dan Penyebabnya Pengamanan tegangan lebih yang terbaik adalah arrester. Ada
kalanya alat pengaman sudah terpasang dengan baik tetapi mengalami kerusakan pada saat terkena sambaran petir baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga menyebabkan kegagalan dalam pengamanan.
Kegagalan pengaman mencakup komponen sebagai berikut:
a) Pada arrester dapat disebabkan antara lain: Sambungan kawat arrester pada terminal arrester tidak baik atau tidak cukup kencang
Sambungan kawat arrester pada kawat fasa jaringan tidak baik atau tidak cukup kencang
Sambungan kawat arrester ke terminal tanah arrester tidak baik atau tidak cukup kencang
Sambungankawat pentanahan arres ter dengan kawat (batang pentanahan) tidak baik atau tidak cukup kencang
Tahanan pentanahan arrester > 1 Ohm
Jarak arester terlalu jauh dari trafo Jarak panjang arrester pada tiang yang satu dengan arrester pada tiang yang lain terlalu jauh
Arrester tidak bekerja optimal, meskipun tidak ada petir menyambar
secara langsung maupun tidak langsung arrester bekerja atau jika ada Pentanahan kawat tanah tidak sempurna (> 1 ohm) misalnya
sambungan pada konektor longgar, elektroda bumi berkarat, perubahan kondisi dan struktur tanah dan sebagainya.
sambaran dan arrester bekerja tapi alat yang diamankan juga rusak. Hal ini disebabkan oleh jarak celah arrester tidak sesuai atau arrester sudah rusak, sehingga perlu diganti dengan yang baru.
Jika arrester meledak karena terkena sambaran petir secara langsung atau tidak langsung baik pada JTM maupun pada arrester, berarti arrester tidak dapat bekerja dan tidak dapat mengubah dirinya menjadi penghantar lagi sehingga arrester juga harus diganti dengan yang baru.
b) Turunnya rodgap/sparkgap (trafo, isolator dan bushing) dapat disebabkan antara lain: Posisi dan jarak antara rodgap pada terminal sekunder trafo GI maupun pada terminal primer trafo distribusi perlu dikembalikan ke posisi dan jarak semula yang benar.
Gambar 6-57 Tegangan pada SKTM akibat sambaran petir pada SUTM
Saklar dan Pengaman
370
Terjadi perubahan konstruksi JTM karena gangguan alam, tiang miring dan sebagainya
c) Perencanaan salah, misalnya penempatan pengaman, penentuan jenis dan ukuran pengaman, koordinasi isolasi, salah pemilihan dan survai tahanan tanah tidak akurat.
d) Pemeliharaan tidak baik pada jaringan trafo, penghantar maupun pada alat pengaman.
Gambar 6-58. Penghantar putus sehingga arus mengalir ke tanah
Rodgap juga perlu dibersihkan dari akumulasi kotoran dan polusi, bushing tua, kotor, retak rambut dan sebagainya.
Isolator kotor perlu dibersihkan dari akumulasi kotoran dan polusi dan retak dan sebagai nya.
Trafo sudah tua atau kualitas tahanan isolasi kumparan menurun
Minyak trafo kotor sehingga banayk mengandung bahan konduktif seperti endapan karbon dan uap/air.
Jarak kawat tanah dengan kawat fasa tidak standar (sudut perlindungan maksimum 45º)
Kawat tanah mengendor
Gambar 6-60. Bushing trafo pecah Gambar 6-59. Kegagalan sambungan
kawat pada terminal trafo
Saklar dan Pengaman
371
6-7-13 Pengawatan Pengaman Pengawatan relai pengaman bertujuan untuk menjadikan seluruh
komponen-komponen perangkat pengaman dapat berfungsi sebagai mana mestinya. Dengan demikian komponen-komponen berfungsi sebagai relai pengaman yang dapat beroperasi menjatuhkan pemutus tenaga atau melepaskan aliran arus dan tegangan jika terjadi gangguan. Komponen-komponen tersebut adalah relai arus lebih (OCR), pemutus tenaga (PMT), trafo arus, trafo tegangan, batery dan kabel kontrol.
Diagram satu garis pengaman jaringan tegangan menengah dapat dilihat pada Gambar 6-62. Bila terjadi gangguan pada penyulang, relai 51 atau 51 N akan bekerja memerintahkan trip pada PMT secara otomatis. Dan relai recloser 79 akan memerintah PMT untuk menutup kembali.
Keterangan: 50/51 = Relai OCR antar fasa dengan penundaan waktu
dikombinasi dengan instant 51 N = Relai hubung tanah
Gambar 6-61. Perangkat Relai Pengaman Arus Lebih
Gambar 6-62. Diagram satu garis pengaman JTM
Saklar dan Pengaman
372
79 = Relai recloser Keterangan:
51 = Relai OCR antar fasa dengan penundaan waktu 676 = Relai gangguan tanah terarah (DGFR) 79 = Relai recloser PT = Trafo tenaga CT = Trafo arus Diagram pengawatan pengaman arus bolak-balik (AC) dengan kendali arus searah (kontrol DC) dapat dilihat pada Gambar 6-64. Diagram pengawatan AC adalah pengawatan dari terminal-terminal trafo arus ke terminal kumparan arus dari relai dan terminal trafo tenaga ke kumparan tegangan dari relai. Diagram kontrol DC adalah pengawatan dari kontak-kontak relai ke terminal kumparan trip dari pemutus tenaga dan baterai.
Gambar 6-63. Pengawatan pengaman dengan relai OCR
Gambar 6-64. Diagram pengawatan AC dengan kontrol DC dari OCR/GFR (Metoda 2 OCP)
Saklar dan Pengaman
373
Bila gangguan terjadi, maka relai OCR (R), OCR (T) dan GFR akan
bekerja, tergantung pada jenis gangguan (fasa atau tanah) sehingga akan menutup kontaknya. Kontak R adalah OCR fasa R dan kontak T adalah OCR fasa T,serta G adalah GFR fasa R. Bila salah satu atau ketiga kontak menutup, maka relai waktu RT akan mendapat tegangan DC dan akan bereaksi untuk menutup kontak D1 sesuai dengan tunda waktunya. Karena D1 menutup, maka triping coil dari PMT (52) akan mendapat tegangan serta membuka PMT. Internal diagram dari relai pengaman diperlukan untuk menentukan terminal-terminal arus DC suplai dan kontak trip.
Daftar Pustaka
373
DAFTAR PUSTAKA
1. Artono Arismunandar, DR. M.A.Sc DR. Susumu Kuwahara. 1975. Buku Pegangan Teknik Tenaga Listrik Jilid I. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
2. Artono Arismunandar, DR. M.A.Sc, DR. Susumu Kuwahara. 1975. Buku Pegangan Teknik Tenaga Listrik Jilid II. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
3. APEI Pusat. 2004. Materi kursus/Pembekalan Uji Keahlian bidang Teknik tenaga Listrik, Kualifikasi : AHLI MUDA. Jakarta: APEI.
4. APEI Pusat. 2006. Materi kursus/Pembekalan Uji Keahlian bidang Teknik tenaga Listrik, Kualifikasi : AHLI MADYA. Jakarta: APEI.
5. Bambang Djaja. 1984. Distribution & Power Transformator. Surabaya : B & D.
6. Bonggas L. Tobing. 2003. Dasar Teknik Pengujian Tegangan Tinggi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
7. Bonggas L. Tobing. 2003. Peralatan Tegangan Tinggi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
8. Daryanto Drs. 2000. Teknik Pengerjaan Listrik. Jakarta: Bumi Aksara.
9. Depdiknas. 2004. Kurikulum SMK 2004 Bidang Keahlian Teknik Distribusi Tenaga Listrik. Dirjen Dikdasmen, Direktorat Dikmenjur.
10. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. 2004. Sosialisasi Standar Latih Kompetensi (SLK) Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik. Jakarta: Pusat Diklat Energi dan Ketenagalistrikan.
11. Imam Sugandi Ir, dkk. 2001. Panduan Instalasi Listrik untuk Rumah berdasarkan PUIL 2000. Jakarta: Yarsa Printing.
12. Naryanto, Ir. & Heru Subagyo, Drs. 1997. Manajemen Gangguan sebagai Upaya Meningkatkan Keandalan Sistem. Surabaya : AKLI DPD JATIM dan DPC SURABAYA.
13. PLN PT. 2003. Workshop Nasional Distribusi. Jakarta: PLN Jasa Diklat
14. PLN UDIKLAT Pandaan. Pemeliharaan Gardu tiang (GTT). 15. PLN Distribusi Jatim. 1997. Pelatihan Koordinator Pelaksana
Pekerjaan Konstruksi Jaring Distribusi. AKLI DPD JATIM dan PLN Distribusi Jatim.
Daftar Pustaka
374
16. PLN Distribusi Jatim. 1997. Konstruksi Jaringan Perusahaan Listrik Negara Distribusi Jawa Timur.
17. PLN Distribusi Jatim. 1997. Pelatihan Tenaga Ahli Kontraktor Listrik. AKLI DPD JATIM dan PLN Distribusi Jatim.
18. Soedjana Sapiie. DR, Osamu Nishino DR. 1982. Pengukuran dan Alat-alat Ukur Listrik. Jakarta: Pradnya Paramita.
19. Standar Nasional Indonesia. 2000. Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000. Jakarta: Yayasan PUIL.
20. Standar Listrik Indonesia. 1988. Gangguan pada Sistem Suplai yang diakibatkan oleh Peranti Listrik dan Perlengkapannya. Jakarta: Departemen Pertambangan dan Energi.
21. Standar Listrik Indonesia. 1988. Spesifikasi Desain untuk Jaringan Tegangan Menengah dan Jaringan Tegangan Rendah. Jakarta: Departemen Pertambangan dan Energi.
22. Standar Listrik Indonesia. 1988. Metode Pengujian yang direkomendasikan untuk Instrumen Ukur Listrik Analog Penunjuk Langsung dan kelengkapannya. Jakarta: Departemen Pertambangan dan Energi.
23. Stam H. N. C. 1993. Keselamatan dan Kesehatan di Tempat Kerja. Penebar Swadaya: Jakarta.
24. Trevor Linsley. 2004. Instalasi Listrik Tingkat Lanjut. Jakarta : Erlangga.
25. Yamanaka. Electric Wire & Cable. Sinar Merbabu: Surabaya
Daftar Istilah
377
DAFTAR ISTILAH admitansi admittance andongan (lendutan) sag 55 arus bolak-balik alternating current arus pemuat charging current arus searah direct current arus yang diperbolehkan allowable current arus current atenuasi attenuation bagian penguat bracing member barang besi hardware batang pelindung armor rod batas elastis elasticity limit beban lawan counterweight beban load berat jenis specific gravity, density berisik noise besi tempaan malleable iron beton pelindung mulching concrete daya power daya-guna efficiency faktor beban load factor faktor daya power factor faktor hilang tahanan annual loss factor faktor keamanan safety factor faktor tegangan lebih overvoltage factor frekuensi frequency gangguan radio radio interference gardu induk substation garis pusat centerline garis-tengah diameter gawang span gaya putar torsional force gejala menghilang fading gelombang berdiri standing wave gelombang lenturan diffracted wave gelombang mikro micro wave gelombang pantulan reflected wave gulungan kerja (operasi) operating coil gulungan pelindung shielding coil gulungan penghambat restraining coil gulungan peredam damper winding gulungan coil, winding hilang kebocoran leakage loss hilang tenaga energy loss hubung singkat short-circuit impedansi surJa surge impedance impedansi impedance induktansi inductance isolator gantung suspension insulator isolator jenis batang-panjang long-rod insulator isolator jenis pasak pin-type insulator isolator jenis pos saluran line-post insulator jam ekivalen tahunan annual equivalent hour kapasitansi capacitance
Daftar Istilah
378
kapasitor capacitor kawat berkas bundled conductor kawat berlilit stranded conductor kawat campuran alloy conductor kawat komponen component wire kawat padat solid conductor kawat paduan composite conductor kawat pelindung shield wire kawat penolong messenger wire kawat rongga hollow conductor kawat tanah ground wire kawat telanjang bare conductor kawat conductor, wire keadaan peralihan transient state keadaan tetap steady state keandalan reliability kearahan directivity kelongsong reparasi repair sleeves kepekaan sensitivity keporian porosity kisi-kisi lattice koeffisien elastisitas elasticity coefficient koeffisien pemuaian linier coefficient of linear expansion koeffisien suhu temperature coefficient komponen simetris symmetrical component konduktansi conductance konduktivitas conductivity konstanta saluran line constants kuat pancang cantilever strength kuat patah breaking strength kuat pikul angkatan, uplift bearing strength kuat pikul tekanan compression bearing strength kuat pikul bearing strength kuat tarik maksimurn ultimate tensile strength kuat tarik tensile stress kuat tindas crushing strength kuat tekan compressive strength kupingan (isolator) shed lintasan route lompatan api flashover lubang kerja manhole panas jenis specific heat panas spesifik specific heat pancang pile pangkal pengiriman sending end pantulan flection papan penahan butting board pasak pengunci lock pin pasangan fitting pekerja saluran lineman pelindung jaringan network protector pemanjangan elongation pembagian beban load dispatching pembawa saluran tenaga power line carrier (PLC) pembumian grounding pemisah disconnect switch pemutus beban cepat high-speed circuit breaker pemutus beban circuit breaker
Daftar Istilah
379
penala tuner, tuning penegang kawat tensioner penemu gangguan fault locator pengait coupling pengapit clamp penghitung counter penguat penerima receiving amplifier penguat penyama matching amplifier pengubah fasa phase modifier penjepit kawat snatch block pentanahan gounding penuntun gelombang wave guide penutup cepat high-speed recloser penyaring filter penyearah rectifier penyeimbang balancer penyetelan adjustment penyokong bracket peralatan hubung (-penghubung) switch gear peralatan pengait line coupling equipment peralatan pengait line coupling equipment peralatan pengubah AC ke DC converter peralatan pengubah DC ke AC inverter peralatan perisaian shielding device peralihan transient perancangan planning perbandingan hubung-singkat short-circuit ratio perbandingan kerampingan slenderness ratio percikan sparkover peredam damper peredaman lihat "atenuasi", damping perentang spacer permitivitas permittivity~ perolehan daya power gain pusat beban load centre Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA) hydro power stations Pusat Listrik Tenaga Termis (PLTT) thermal power station Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD) diesel power stations Pusat Listrik Tenaga Gas (PLTG) gas-fired power station pusat-pusat listrik power stations rambatan propagation rangkaian ganda double circuit rangkaian monitor penghambat- delay monitor circuit rangkaian tunggal single circuit reaktansi reactance regulasi tegangan voltage regulation relc pencatat gangguan fault locating relay rele arah directional relay rele arus lebih overcurrent relay rele daya power relay rele diferensial differential relay rele firkwensi frequency relay rele gelombang mikro microwave relay rele impedansi impedance relay rele jarak distance relay rele konduktansi conductance relay rele Mho Mho relay rele offset-Mho Offset-Mho relay
Daftar Istilah
380
rele penutup kembali reclosing relay rele penutupan closing relay rele penyalur transmitter relay rele pernbawa saluran power line carrier relay rele pilot-kawat wire-pilot relay rele reaktansi reactance relay rele suseptansi susceptance relay rele tahanan resistance relay rele tegangan kurang undervoltage relay rele tegangan lebih overvoltage relay resistivitas resistivity respon penguat exciter response ril, rel bus rugi daya tranmisi transmission loss rugitahanan resistance loss s I arung (kabel) (cable) sheath saluran bawah tanah underground line saluran bertegangan hot-line saluran ganda double-circuit transmission line saluran komunikasi communication channel saluran panas hot-line saluran penghubung feeder line saluran tertutup loop transmission line saluran transmisi transmission line saluran udara overhead line sela batang rod gap sela pelindung protective gap semu appearance sentral. listrik Iihat Pusat Listrik siku pelindung mulching angle sistim banyak-terminal multi-terminal system sistim berturutan tandem system sistim jaringan spot-network system sistim rangkaian tertutup loop system stabilitas peralihan transient stability stabilitas tetap steady state stability stasion jinjingan portable station stasion mobil mobile station stasion pangkalan base station stasion tetap fixed station struktur pasak pin structure sudut ayun swing angle surja hubung switching surge surja surge survey garis pusat center line survey survey lokasi menara tower site study survey profil. profile survey survey tampak atas plan survey suseptansi susceptance tahanan jenis resistivity tahanan resistance tanduk (busur) api arcing horn tangkai operasi operating shaft tegangan geser shearing stress tegangan harian everyday stress (EDS) tegangan kejut pulse voltage tegangan ketahanan withstand voltage tegangan lebih dalam internal overvoltage
Daftar Istilah
381
tegangan lebih overvoltage tegangan lentur bending stress tegangan lumer yielding stress tegangan patah breaking strength tegangan perencanaan design stress tegangan pikul bearing stress tegangan tarik tensile stress tegangan tekan compression stress tegangan serat fibre stress tenaga energy titik lebur melting point ugi pancaran propagation loss ujung penerimaan receiving end urutan negatip negative sequence urutan nol zero sequence urutan positip positive sequence waktu mati dead time waktu membuka opening time waktu menutup making time waktu pasang kembali resetting time
Tabe
l 5-3
. Jen
is-je
nis
Fasi
litas
Kom
unik
asi
Sal
uran
Ata
s Ta
nah
Sal
uran
Tel
epon
Sen
diri
Tr
ansm
isi F
reku
ensi
sua
ra
Salu
ran
yang
dip
asan
g
Tele
koun
ikas
i
Pa
da T
iang
Sal
uran
Ten
aga
Kom
unik
asi d
enga
n Fr
ekue
n-
M
elal
ui k
awat
(T
rans
mis
i ata
u D
istri
busi
)
si P
emba
wa
(Car
rier)
dan
kabe
l
Sa
lura
n Ka
bel U
dara
(Sen
diri
Tran
smis
i Fre
kuen
si S
uara
Ka
bel
atau
Ber
sma
yang
lain
)
Salu
ran
Kabe
l Tan
ah
Ko
mun
ikas
i den
gan
Frek
uen-
Te
leko
mun
ikas
i
Tele
kom
unik
asi
Sa
lura
n Tu
ngga
l
si P
emba
wa
(Car
rier)
un
tukI
ndus
tri
m
elal
ui P
emba
wa
Tena
gaLi
strik
Salu
ran
Tena
ga
Sa
lura
n Ba
nyak
(PLC
)
(M
ultip
le C
hann
el)
Te
tap
Tem
patn
ya
Gel
omba
ng P
ende
k
M
obil
(unt
uk p
emel
ihar
aan)
Mob
il (u
ntuk
pem
elih
araa
n
Te
ruta
ma
150
Hz
band
)
VH
F (V
ery
Hig
h Fr
eque
nsi)
(2-3
00 M
Hz)
S
atu
salu
ran
(teru
tam
a 60
Tele
kom
unik
asi
MH
z)
R
adio
Teta
p
Ban
yak
salu
ran
(teru
tam
a
Mob
il (u
ntuk
pem
elih
araa
n)
160
MH
z)
400
MH
z ba
nd
Teta
p, B
anya
k sa
lura
n
G
elom
bang
Mik
ro
(di a
tas
1.00
0 M
.Hz)
T
etap
, Ban
yak
salu
ran
275
DIA
GR
AM
PEN
CA
PAIA
N K
OM
PETE
NSI
D
iagr
am in
i men
unju
kkan
taha
pan
atau
tata
uru
tan
kom
pete
nsi y
ang
diaj
arka
n da
n di
latih
kan
kepa
da p
eser
ta d
idik
da
lam
kur
un w
aktu
yan
g di
butu
hkan
ser
ta k
emun
gkin
an m
ulti
exit-
mul
ti en
try y
ang
dapa
t dite
rapk
an.
DIS
.KO
N.0
01(2
) D
IS.K
ON
.002
(2A
D
IS.K
ON
.003
(2)
DIS
.KO
N.0
04(2
) D
IS.K
ON
.005
(2)
DIS
.KO
N.0
11(1
) D
IS.K
ON
.013
(1)
DIS
.KO
N.0
06(2
)
DIS
.KO
N.0
18(2
)
DIS
.KO
N.0
25(1
)
TEK
NIS
I PE
MA
SAN
GA
N
APP
-TM
TEK
NIS
I PE
MA
SAN
GA
N
JAR
ING
AN
TM
TEK
NIS
IPE
MA
SAN
GA
N
APP
-TR
TEK
NIS
I PE
MA
SAN
GA
N
DIS
TRIB
USI
TEK
NIS
I PEM
ASA
NG
AN
KO
NST
RU
KSI
D
ISTR
IBU
SI
DIS
.KO
N.0
10(2
) D
IS.K
ON
.014
(2)
DIS
.KO
N.0
19(2
) D
IS.K
ON
.016
(2)
DIS
.KO
N.0
08(1
) D
IS.K
ON
.012
(2)
DIS
.KO
N.0
09(2
) D
IS.K
ON
.015
.(2)
DIS
.KO
N.0
17(2
) D
IS.K
ON
.020
(2)
DIS
.OPS
.001
(2)
DIS
.OPS
.002
(2)
DIS
.OPS
.003
(2)
DIS
.OPS
.004
(2)
DIS
.OPS
.007
(2)
DIS
.OPS
.009
(2)
DIS
.OPS
.013
(2)
DIS
.HA
R.0
01(2
)
DIS
.HA
R.0
02(2
) D
IS.H
AR
.003
(2)
DIS
.HA
R.0
35(2
)
DIS
.HA
R.0
37(1
)
DIS
.HA
R.0
39(2
)
DIS
.OPS
.006
(2)
DIS
.OPS
.014
(2)
DIS
.OPS
.015
(2)
DIS
.OPS
.016
(2)
DIS
.OPS
.005
(2)
DIS
.OPS
.008
(2)
DIS
.OPS
.011
(2)
OPE
RA
TOR
JA
RIN
GA
N
DIS
TRIB
USI
TM
DIS
.HA
R.0
04(2
)
TEK
NIS
I PE
MEL
IHA
RA
AN
D
ISTR
IBU
SI L
ISTR
IK
TEK
NIS
I PE
MEL
IHA
RA
AN
A
PP
TEK
NIS
I PEM
ELIH
ARA
N
PER
ALA
TAN
SC
AD
A
OPE
RA
TOR
JA
RIN
GA
N
DIS
TRIB
USI
TR
DIA
GR
AM
PEN
CA
PAIA
N K
OM
PETE
NSI
TE
KN
IK L
ISTR
IK D
ISTR
IBU
SI
Ir. Suhadi. Lahir di Malang, tgl. 2 Maret 1947. Pendidikan SRN di Malang tamat tahun 1961. Pendidikan STN IV (Listrik) di Surabaya tamat tahun 1965 dan STMN I (Listrik) tahun 1968 di kota yang sama. Gelar Sarjana S-1 Teknik Elektro diperoleh di Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya pada tahun 1979. Akta V diperoleh di Universitas Terbuka Jakarta tahun 1984. Sejak tahun 1980 diangkat sebagai dosen tetap (PNS) di Jurusan Teknik Elektro FT. UNESA. Tahun 1979 s.d tahun 1989 sebagai penanggung jawab teknik kontraktor listrik CV. Pancasila Surabaya. Tahun 1991 hingga 1999 sebagai Ketua Lab. Teknik Elektro FT. UNESA dan tahun 1999 hingga tahun 2003 menjabat sebagai Ketua Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik UNESA. Sebagai Ketua Program Studi Teknik Listrik Industri dan dosen Politeknik Madiun, sejak tahun 2004 sekarang. Sebagai dosen SUSGADIK di AAL dan STTAL Bumimoro Surabaya, sejak tahun 2005 hingga sekarang. Penelitian yang pernah dilakukan adalah Uji coba Buku Siswa Mata Pelajaran Konsep Dasar Listrik dan Elektro berorientasi Kontekstual di SMK kelompok Teknologi dan Rekayasa. Organisasi profesi yang diikuti adalah Himpunan Ahli Elektro Indonesia (HAEI) Jawa Timur, sebagai Ketua Bidang Elektronika dan Telekomunikasi, sejak 1998 hingga sekarang. Drs. Tri Wrahatnolo, M.Pd, MT. Lahir di Malang, tgl. 27 Januari 1962. Pendidikan SDN di Blitar tamat tahun 1974. Pendidikan SMPN di Blitar tamat tahun 1977 dan STMN (Listrik) tahun 1981 di kota yang sama. Gelar Sarjana S-1 diperoleh di IKIP Negeri Surabaya (UNESA) Bidang Studi Pendidikan Teknik Elektro tamat tahun 1986. Pendidikan S-2 di IKIP Negeri Jakarta (UNJ) tamat tahun 1992 bidang Studi Pendidikan Teknologi Kejuruan, Pra S-2 Teknik Elektro tamat tahun 1998 dan S-2 Teknik Sistem Tenaga Listrik tamat tahun 2001 di ITS Surabaya. Sejak tahun 1987 diangkat sebagai dosen tetap di Jurusan Teknik Elektro FT. UNESA. Tahun 1991-1993 sebagai Ka. Lab. Konversi Energi Jurusan TE-FT. UNESA, Tahun 1993-1997 sebagai Ka.Unit Layanan Komputer Dosen. Pembantu Dekan I FT. UNESA tahun 1993 hingga sekarang. Sebagai Tutor UT-UPBJJ Surabaya 2001 hingga sekarang. Asisten Direktur I dan dosen Politeknik Madiun tahun 2003-2004. Sebagai dosen Sustedik, KODIKAL Bumimoro Surabaya tahun 1993-1997 dan sebagai dosen Susgadik, KODIKAL Bumimoro Surabaya tahun 1994-1995. Instruktur Dinas Kimpraswil Surabaya tahun 2001, sebagai Anggota Dewan Majelis Pertimbangan LPJK Jawa Timur sejak 2004 hingga sekarang, Sub Kontraktor Listrik di PT. Balfour Beaty Sakti Indonesia di Surabaya 1986-1987. Sekretaris Asosiasi Pendidikan Teknologi Kejuruan Wilayah Jawa Timur, 2004 hingga sekarang.
JGV"*Jctic"Gegtcp"Vgtvkpiik+"Tr0"90:::.22
KUDP"ZZZ/ZZZ/ZZZ/Z
Dwmw"kpk"vgncj"fkpknck"qngj"Dcfcp"Uvcpfct"Pcukqpcn"Rgpfkfkmcp"*DUPR+"fcp"vgncj"fkpcvcmcp" nccm" ugdcick" dwmw" vgmu" rgnclctcp" dgtfcuctmcp" Rgtcvwtcp" Ogpvgtk"Rgpfkfkmcp"Pcukqpcn"Pqoqt"68"Vcjwp"4229" vcpiicn"7"Fgugodgt"4229" vgpvcpi"Rgpgvcrcp"Dwmw"Vgmu"Rgnclctcp"cpi"Ogogpwjk"Uctcv"Mgnccmcp"wpvwm"Fkiw/pcmcp"fcnco"Rtqugu"Rgodgnclctcp0
Teknik Distribusi TenagaListrik Suhadi
Tri Wrahatnolo
untukSekolah Menengah Kejuruan
Su
had
i | Tri Wrah
atno
lo
TE
KN
IK D
IST
RIB
US
I TE
NA
GA
LIS
TR
IK
un
tuk S
MK
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah KejuruanDirektorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan MenengahDepartemen Pendidikan Nasional
HET (Harga Eceran Tertinggi) Rp. 7.888,00
ISBN XXX-XXX-XXX-X
Buku ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah dinyatakan layak sebagai buku teks pelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2007 tanggal 5 Desember 2007 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digu-nakan dalam Proses Pembelajaran.