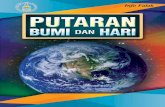Avventure di un'avventuriera. Le note di viaggio (in Sicilia) di Marija Puare
Sensasi Partisipasi Demokratik di antara Pengguna Media Baru di Indonesia: Studi Kasus Pemilukada...
Transcript of Sensasi Partisipasi Demokratik di antara Pengguna Media Baru di Indonesia: Studi Kasus Pemilukada...
1
Draft untuk The 3rd Indonesian International Conference on Communication
(IndoICC) 2015, Dep. Komunikasi, Universitas Indonesia.
Sensasi Partisipasi Demokratik di antara Pengguna Media Baru di Indonesia:
Studi Kasus Pemilukada Jakarta Putaran Kedua
Oleh:
Hizkia Yosie Polimpung1
Koperasi Riset PURUSHA
Ikhtisar
Penelitian ini berangkat dari sebuah paradoks dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia hari‐
hari ini: maraknya kehadiran media massa, terutama media baru, berikut intensitas penggunaan
yang super tinggi di satu sisi, sementara maraknya opini publik tentang demokrasi yang belum
benar‐benar diimplementasikan, bahkan tidak sedikit yang secara pesimis menilainya sebagai
kegagalan. Jadi, di satu sisi terdapat surplus media, dan di sisi lain terdapat defisit demokrasi.
Kenyatan inilah yang disebut sebagai ‘paradoks demokratisasi di era media baru’. Paradoks ini
akan berubah menjadi suatu anomali saat ia dibenturkan dengan teori klasik yang menekankan
peran media sebagai pilar keempat demokrasi (setelah eksekutif, legistlatif dan yudikatif). Media,
diyakini menjadi prasyarat mutlak sekaligus indikator penting bagi terselenggaranya demokrasi.
Dengan latar belakang teoritik seperti ini, dengan demikian penelitian ini mengajukan
pertanyaan, “mengapa di era keterbukaan informasi dimana hampir seluruh orang dapat
mengartikulasikan pendapatnya secara bebas melalui media, malah muncul wacana defisit
demokrasi?”
Penelitian ini menggunakan analisis simtom‐wacana psikoanalisis Jacques Lacan untuk
memecahkan permasalahan ini. Teori ini melihat prilaku subyek, dalam hal ini, partisipasi
demokrasi sebagai sebentuk upaya untuk memenuhi hasratnya. Akibatnya, pemenuhan hasratlah
yang menjadi utama, ketimbang tindakan partisipasi tersebut. Untuk memperoleh hasrat ini,
subyek tidak perlu benar‐benar berpartisipasi, ia cukup hanya perlu merasakan sensasi
berpartisipasi. Sensasi inilah yang sebenarnya ia cari melalui tindakan yang ia kira partisipasi
demokrasi—nyatanya, tidak ada yang terjadi secara kongkrit di lapangan. Adalah media baru
yang mampu mengkondisikan kesalah‐mengiraan ini, sehingga ia mampu menjebak energi‐
energi partisipasi subyek di dalam sirkuit medianya dengan cara terus menerus memproduksi
sensasi partisipasi demokrasi.
Untuk menunjukkan ini, penelitian akan melakukan evaluasi pada partisipasi masyarakat melalui
media dengan menganalisis 1000 buah “kicauan” (tweet) masyarakat di sekitar Pemilihan
1 Makalah ini dimungkinkan melalui riset dengan judul ‘Defisit Demokrasi vs Surplus Media: Paradoks
Demokratisasi di Indonesia pada Era Media Baru’ yang terselenggara oleh sokongan dana dari Hibah Riset DRPM
Universitas Indonesia 2011. Penulis juga berterima kasih kepada PACIVIS Center for Global Civil Society Studies
yang memfasilitiasi pelaksanaan kegiatan‐kegiatan yang tercakup di riset ini, dan juga bagi asistensi yang amat
berharga dari Mita Yesyca dan Levriana Yustriani. Terima kasih juga disampaikan kepada tim analis tweets yang
membantu pengolahan data: yaitu Frisca Tobing, Melia Halim, Fityananda Musthika, Elda Claudia Sembiring, dan
Debora Widawati.
2
gubernur Jakarta putaran kedua, melalui platform mikro‐blog Twitter. Pola dominan hasrat akan
dipetakan sebarannya, untuk kemudian ditunjukkan sensasi partisipasi demokrasi seperti apa
yang diproduksinya. Penelitian ini akan diakhiri dengan menyimpulkan apa artinya temuan‐
temuan ini bagi konsep dan praktik partisipasi demokrasi di era media baru.
Kata Kunci: demokrasi; hasrat; identitas hasrat; obyek hasrat; partisipasi; sensasi; media baru.
Partisipasi Demokrasi di Era Media Baru
Setelah Reformasi, Indonesia dilihat menjadi salah satu negara dengan
perkembangan demokrasi yang paling cepat. Pandangan ini terutama muncul setelah
banyak orang yang melihat pemilihan‐pemilihan umum berjamuran di mana‐mana—
baik dari level kepala desa hingga Presiden. Selain itu, juga muncul perubahan‐
perubahan lain di struktur pemerintahan, seperti pendirian Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), yang diharapkan dapat menghentikan berbagai praktik korupsi yang
selama ini masih merajalela di berbagai institusi pemerintahan. Bahkan Menteri Luar
Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton pernah memuji Indonesia sebagai role‐model,
khususnya bagi Myanmar dan negara‐negara di Timur Tengah, karena telah mengalami
transisi dari pemerintahan yang otoritarian menuju demokrasi yang tumbuh pesat
dengan populasi yang mayoritas Muslim.2 Meskipun terdapat seluruh perkembangan ini,
masih tersisa pertanyaan: Apakah demokrasi yang terjadi di Indonesia benar‐benar
setara, menyeluruh, dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di negara ini?
Jika Demokrasi terdiri dari tiga pilar—eksekutif, legislatif dan yudikatif, maka
pilar keempatnya adalah media yang independen.3 Hal ini berarti bahwa kebebasan
berpendapat di media serta intensitas diskusi mengenai demokrasi di media menjadi
salah satu indikator terwujudnya demokrasi. Namun, faktanya di Indonesia hampir
keseluruhan dari partisipasi masyarakat di internet adalah untuk bersosialisasi dalam
media jejaring sosial. Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam diskusi tentang
demokrasi di media masih sangat sedikit.
Di sini masalah yang muncul adalah defisit demokrasi, yang disebut oleh Benny
Susetyo sebagai keadaan di mana rakyat terjebak oleh “formalisme,” di mana segala
prosedur yang berkaitan dengan demokrasi—seperti pemilihan umum dan sebagainya—
dijalankan namun tanpa ada makna sesungguhnya untuk memenuhi kepentingan
masyarakat.4 Oleh karena itu, ide dasar riset ini bertujuan untuk mencari cara bagaimana
untuk mengurangi defisit demokrasi yang terjadi di Indonesia ini, yang antara lain
disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat di dalam media.
2 Matthew Lee, “Clinton: Indonesia can be democratic role model” diakses dari
http://www.thejakartapost.com/news/2011/07/24/clinton‐indonesia‐can‐be‐democratic‐role‐model.html/ pada
tanggal 20 September 2011, pukul 8.14 WIB. 3 Julianne Schultz, Reviving the Fourth Estate: Democracy, Accountability and the Media (Cambridge : Cambridge
Un, 1998). 4 Benny Susetyo, “Defisit Demokrasi” dalam Kompas (30 April 2007) diakses dari
http://www.demosindonesia.org/program/advokasi/kampanye/3127‐defisit‐demokrasi.html/ pada tanggal 20
September 2011, pukul 8.28 WIB.
3
Defisit Demokrasi di Indonesia
Benny Susetyo dari Demos Indonesia (sebuah lembaga kajian demokrasi dan
HAM), melihat bahwa defisit demokrasi lama‐kelamaan terjadi di Indonesia. Demokrasi
yang sehat seharusnya terjadi bila muncul penegakan hukum yang bebas dari
kepentingan politik dan kekuasaan, namun makna ini ternyata mengalami defisit di
Indonesia. Defisit demokrasi ini terjadi karena rakyat sudah dijebak oleh yang dinamakan
sebagai “formalisme,” yang berarti apa yang sudah menjadi cita‐cita dan garis besar yang
sudah ditulis dan disepakati makin jauh dari yang seharusnya dipraktikkan. Di sini,
hukum hanya menjadi ornamen, kesejahteraan sosial semata‐mata tulisan dalam
konstitusi, dan perilaku penguasa makin menjauhi amanat konstitusi. Demokrasi pun
hanya sebatas “alat untuk memilih pemimpin” dan tampil sebagai simbol belaka. Rakyat
pun hanya menjadi objek yang dipermainkan oleh para elite dan tidak dapat benar‐benar
berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.5
Hal senada juga diungkapkan oleh Zuly Qodir yang menganggap bahwa defisit
demokrasi di Indonesia hanya berjalan lancar dalam prosesnya tetapi minus etika dan
minus substansi.6 Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa konsep partisipasi
masyarakat berkaitan dengan konsep keterbukaan. Dalam artian, tanpa keterbukaan
pemerintahan tidak mungkin masyarakat dapat melakukan peranserta dalam kegiatan‐
kegiatan pemerintahan.7Menurut Hadjon, keterbukaan, baik “openheid” maupun
“openbaar‐heid” sangatpenting artinya bagi pelaksanaan pemerintahan yang baik dan
demokratis. Dengan demikianketerbukaan dipandang sebagai suatu asas ketatanegaraan
mengenai pelaksanaan wewenangsecara layak. Konsep partisipasi terkait dengan konsep
demokrasi, sebagaimana dikemukakan oleh Hadjon bahwa sekitar tahun 1960‐an muncul
suatu konsep demokrasi yang disebut demokrasi partisipasi. Dalam konsep ini rakyat
mempunyai hak untuk ikut memutuskan dalam proses pengambilan keputusan
pemerintahan.8
Mark E. Warren membedakan dua jenis masalah partisipatif dalam masalah defisit demokrasi yang lebih luas.9 Yang pertama, defisit dalam lembaga formal demokrasi elektoral, baik yang diakui dan sering diteliti. Yang kedua adalah lebih baru dan khas: defisit yang telah muncul dalam banyak bentuk baru 'keterlibatan warga negaraʹ, yang telah dikembangkan untuk menanggapi defisit dalam demokrasi elektoral. Jenis pertama defisit ini membutuhkan reformasi kelembagaan, seperti desain ulang sistem pemilu, lembaga parlemen, dan perubahan konstitusi dasar, sehingga mereka lebih responsif, dan memiliki kapasitas lebih besar untuk
5 Benny Susetyo, “Defisit Demokrasi,” Loc. Cit. 6 “Kecenderungan Terjadinya Defisit Demokrasi 2009” diakses dari
http://csps.ugm.ac.id/indonesian/Kecenderungan‐Terjadinya‐Defisit‐Demokrasi‐2009.html/ pada tanggal 20
September 2011, pukul 8.31 WIB. 7 Pidato Philipus M. Hadjon, 1997 dalam Ni Made Ari Yuliartini Griadhi dan Anak Agung Sri Utari,
“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah”, Kertha Patrika Vol. 33 No. 1, Januari 2008. 8 Ibid., 9 Mark E. Warren, “Citizen Participation and Democratic Deficits: Considerations from the Perspective of
Democratic Theory”, hal. 2 diakses melalui
http://www.politics.ubc.ca/fileadmin/user_upload/poli_sci/Faculty/warren/Citizen_Participation_and_Democrati
c_Deficits_Draft_5.pdf
4
mengumpulkan informasi, musyawarah, dan pembentukan kebijakan. Jenis kedua defisit
memerlukan penyesuaian pada lembaga yang sudah ada seperti merancang bentuk‐
bentuk baru demokrasi yang suplemen dan melengkapi lembaga‐lembaga formal
demokrasi elektoral, terutama di daerah‐daerah kebijakan fungsional dimana lembaga
pemilu masih memiliki kapasitas yang lemah untuk menghasilkan demokrasi legitimasi.
Saat ini orang melihat munculnya defisit demokrasi, yakni kesenjangan antara
proses dan mekanisme pembuatan keputusan dengan keputusannya sendiri. Singkatnya,
sekalipun setiap warga negara secara aktif berpartisipasi dalam proses pembuatan
keputusan, keputusan yang diambil lebih banyak ditentukan oleh mereka yang tidak
memiliki privilege politik dalam proses demokrasi seperti misalnya perusahaan‐
perusahaan multinasional, organisasi‐organisasi internasional ataupun insitusi dan
kepentingan dari luar batas‐batas komunitas politik tersebut10 Memang, satu hal yang
patut dicatat dan harus mendapat perhatian serius adalah bahwa demokrasi ternyata
tidak menjamin adanya partisipasi. Demokrasi hanya menyediakan ruang‐ruang publik
dan membiarkan ruang publik itu diisi oleh partisipasi aktif rakyat. Dengan kerangka
demikian, maka partisipasi merupakan pilihan dari rakyat untuk memanfaatkan ruang
publik. Ruang publik yang sudah terbuka tersebut memang idealnya harus diisi oleh
partisipasi aktif rakyat, dan sekali lagi itu adalah mutlak tugas dan kewajiban rakyat itu
sendiri. Dalam situasinya yang ideal, memang ruang publik harus diisi oleh partisipasi
aktif rakyat untuk melakukan deliberasi dan membuat diskursus. Akan tetapi, jika rakyat
tidak mampu mengisi ruang‐ruang publik tersebut dengan partisipasi, maka yang terjadi
adalah ruang‐ruang tersebut didominasi oleh para elit‐elit yang pragmatis dan hanya
mengejar sumber daya politik maupun ekonomi, sehingga yang muncul bukanlah
partisipasi rakyat, melainkan partisipasi elit.
Dari berbagai diskursus di atas, tampak bahwa demokrasi di Indonesia hanya
semata‐mata menjalankan prosedur yang ada—terutama melalui berbagai pemilihan
umum yang dijalankan—tanpa adanya pemenuhan kepentingan rakyat. Dari sini, dapat
dilihat pula bahwa partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi masih sangat minim;
kebanyakan hanya sebatas untuk menjalani formalitas untuk memilih calon pejabat.
Media‐media massa yang ada pun seringkali dibumbui oleh kepentingan pihak‐pihak
politik tertentu dan publik semata‐mata menjadi penonton tanpa dapat berpartisipasi di
dalamnya.
Tetapi belakangan ini, muncul juga fenomena lain yang baru di negara ini, yakni
surplus pengguna jejaring sosial.
Surplus Pengguna Jejaring Sosial
Indonesia tercatat sebagai negara dengan tingkat pengguna internet, terutama
dalam kategori jejaring sosial yang sangat tinggi di dunia. Pada Januari 2011, tercatat
sekitar 31 juta rakyat Indonesia, atau seperdelapan dari 242 juta orang menggunakan
10 Muhadi Sugiono, “Demokrasi dan Dinamika Globalisasi”, hal 2 diakses melalui
http://msugiono.staff.ugm.ac.id/publikasi/demokrasi‐dinamika‐global.pdf
5
internet.11 Jumlah pengguna internet tersebut didominasi oleh pengguna situs jejaring
sosial, antara lain Facebook dan Twitter. Berdasarkan data dari Google AdPlanner pada
Mei 2011, rata‐rata pengguna internet di Indonesia mengakses WordPress selama 8 menit,
Blogspot selama 10 menit, Twitter selama 16 menit, Facebook selama 28 menit, dan
Kaskus selama 30 menit setiap harinya.12 Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar
aktivitas masyarakat Indonesia di dunia maya adalah untuk bersosialisasi melalui situs
jejaring sosial maupun blog.
Indonesia merupakan negara pengguna Facebook terbesar kedua di dunia setelah
AS, dengan jumlah pengguna sebanyak 40.146.340 orang per 17 September 2011.13 Dalam
kurun waktu 6 bulan terakhir, jumlah ini terus meningkat pesat, yang menggambarkan
bahwa budaya bersosialisasi di internet semakin meluas
Berikut grafik jumlah pengguna Facebook pada bulan Maret – Agustus 201114:
Grafik 1. Jumlah Pengguna Facebook di Indonesia Periode Maret – Agustus 2011
11 Ismira Lutfia, “Indonesia’s Social Media Obsession Seen Changing Rules of Marketing”, diakses dari
http://www.thejakartaglobe.com/home/indonesias‐social‐media‐obsession‐seen‐changing‐rules‐of‐
marketing/416821, pada 19 September 2011 pukul 20.00 WIB. 12 _____, “Social Media Impact on Indonesian Internet Users”, diakses dari
http://www.jakartaupdates.com/1639‐07/social‐media‐impact‐on‐indonesian‐internet‐users, pada 19 September
2011 pukul 21.47 WIB. 13 Data dari CheckFacebook.com, diakses dari http://www.checkfacebook.com/ pada 19 September 2011 pukul
19.30 WIB. 14 _____, “Indonesia Facebook Statistics”, diakses dari http://www.socialbakers.com/facebook‐
statistics/indonesia pada 20 September 2011 pukul 09.00 WIB.
6
Grafik 2. Distribusi Umur Pengguna Facebook di Indonesia15
Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa mayoritas pengguna Facebook berada
pada rentang usia 18‐24 tahun dan diikuti oleh pengguna dengan rentang usia 25‐34
tahun. Hal ini menunjukkan bahwa para pengguna Facebook berada pada usia yang
produktif. Selain itu, data statistik dari social bakers16 menunjukkan bahwa tingkat
penetrasi Facebook di Indonesia sebesar 16,52% dibandingkan dengan populasi negara
dan sebesar 133,82% dibandingkan dengan jumlah pengguna internet.17 Tingkat penetrasi
yang sangat tinggi ini memperlihatkan betapa mendominasinya Facebook dalam
aktivitas internet yang dilakukan masyarakat Indonesia.
Sementara itu, dalam jejaring sosial lainnya, yakni Twitter, Indonesia menempati
peringkat ketiga dalam kategori negara dengan jumlah pengguna Twitter tertinggi,
dengan kontribusi sebesar 2,34% terhadap jumlah tweet di dunia pada masa itu.18
Tingginya aktivitas masyarakat Indonesia yang tinggi di jejaring sosial terlihat dari
seringnya tweet yang menjadi trending topic merupakan tweet yang berasal dari pengguna
Twitter di Indonesia. Bahkan, Jakarta merupakan satu‐satunya kota di Asia yang
menempati peringkat 15 besar.19 Artikel The Economist pada 6 Januari 2011 yang berjudul
“Eat, Pray, Tweet”, menuliskan betapa aktifnya pengguna internet di Indonesia dalam
mengakses situs jejaring sosial, yang menggambarkan dengan jelas tentang budaya
Indonesia yang terbuka terhadap jejaring sosial.20
Paradoks Demokrasi di Era Media Baru
Sampai di sini, kita dihadapkan pada dua kenyataan yang bertolak belakang: di
satu sisi wacana mengenai defisit demokrasi merebak di kalangan opinion leader
15 Ibid. 16 Social bakers merupakan badan yang mempublikasikan statistik media sosial yang memfokuskan pada
situs jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan Linkedln. Info mengenai social bakers dan publikasinya dapat
dilihat di www.socialbakers.com. 17 _____, “Indonesia Facebook Statistics”, diakses dari http://www.socialbakers.com/facebook‐
statistics/indonesia, pada 20 September 2011 pukul 09.00 WIB. 18 Ibid. 19 Ibid. 20 _____, “Eat, Pray, Tweet”, dalam The Economist, diakses dari http://www.economist.com/node/17853348
pada 19 September 2011 pukul 21.50 WIB.
7
Indonesia, dan di satu sisi terjadi surplus tinggi atas pengguna media sosial. Dua hal ini
menjadi ironis apabila diletakkan pada anggapan umum bahwa media merupakan pilar
keempat demokrasi. Sebagai pilar keempat demokrasi, media memiliki fungsi penting
dalam demokrasi untuk menjadi saluran partisipasi demokratis masyarakat, yang
notabene krusial sebagai bentuk checks and balances bagi pemerintah yang berkuasa. Pilar
keempat ini, dengan demikian melengkapi ketiga pilar sebelumnya—eksekutif, legislatif,
dan yudikatif.
Tingginya angka pengguna media di Indonesia, apabila dihubungkan dengan
teori pilar keempat demokrasi, maka seharusnya sudah menjadi tidak relevanlah wacana‐
wacana mengenai demokrasi defisit. Logikanya, demokrasi menjadi defisit apabila
masyarakat tidak banyak yang berpartisipasi, sehingga elit mendominasi keseharian
pemerintahan. Hal ini mungkin untuk terjadi, salah satunya apabila saluran‐saluran
untuk menyalurkan aspirasi dan partisipasi adalah sedikit. Namun, kenyataannya justru
sebaliknya. Media, sebagai saluran partisipasi demokratis masyarakat tersebut terbukti
amatlah banyak. Bahkan, penggunaan media baru, yang karenanya rakyat dimungkinkan
untuk berpartisipasi secara ral time, di Indonesia menunjukkan angka yang bukan main
besarnya. Lalu mengapa partisipasi demokrasi menjadi defisit? Kondisi ini yang kami
sebut sebagai paradoks demokrasi di era media baru.
Tepat di sinilah penelisikan kembali mengenai posisi dan peran media dalam
memfasilitasi partisipasi demokrasi hari ini. Ada dua hal yang bisa jadi menjadi problem
utama di sini, yaitu apakah peran media dalam demokrasi telah bergeser dari yang
sebagaimana dimaksudkan teori pilar keempat, atau justru telah terjadi pergeseran
konsep partisipasi demokratis itu sendiri yang memungkinkan terjadinya paradoks ini?
Yang manapun jawabannya, hal paling penting untuk ditelaah lebih lanjut adalah
kondisi‐kondisi apa yang memungkinkan terjadinya pergeseran tersebut. Pertanyaan‐
pertanyaan inilah yang menjadi titik problematika awal kemana studi ini melangkah.
Untuk memecahkan misteri paradoks demokrasi di era media baru ini, pertanyaan yang
diajukan adalah sebagai berikut: “Mengapa di era keterbukaan informasi dimana hampir
seluruh orang dapat mengartikulasikan pendapatnya secara bebas melalui media, malah
muncul wacana defisit demokrasi?”
Melihat kesenjangan yang tinggi antara defisit demokrasi dan surplus social media,
maka penting untuk melakukan upaya‐upaya untuk mengalihkan partisipasi yang tinggi
dalam social media tersebut ke dalam ranah demokrasi. Selain itu, hal ini juga penting
mengingat kehadiran media sebagai pilar keempat dari demokrasi, sehingga dermokrasi
baru akan terwujud sepenuhnya setelah pilar keempat tersebut terwujud.
Peneliti melihat bahwa salah satu solusi yang dapat ditawarkan untuk
memecahkan masalah ini adalah dengan memanfaatkan fakta bahwa Indonesia memiliki
jumlah pengguna social media yang menempati salah satu peringkat paling banyak di
dunia. Sehingga studi ini berusaha melihat kemungkinan apakah partisipasi masyarakat
Indonesia yang besar di ranah jejaring sosial dapat diarahkan untuk membantu
8
mengurangi defisit demokrasi yang terjadi di Indonesia serta mendorong terjadinya
proses demokratisasi yang lebih partisipatif di negara ini.
Lebih lanjut, studi ini dimaksudkan untuk memikirkan kembali hubungan antara
media, demokrasi, dan partisipasi komunikasi di era kontemporer. Tim peneliti
bermaksud untuk melihat dan mengetahui bagaimana media dapat menjadi alat yang
berguna bagi perwujudan demokrasi. Hasil studi nanti diharapkan dapat turut
berkontribusi dalam upaya pemberian edukasi tentang media di kalangan masyarakat
Indonesia.
Psikoanalisis dan Prilaku Partisipatif
Teori‐teori yang membahas mengenai prilaku biasanya akan bertumpu pada
penjelasan rasionalistik ekonomi dan penjelasan psikologis. Penjelasan rasionalistik
biasanya menggunakan teori‐teori seperti teori pilihan rasional dan teori permainan.
Sekalipun terdapat perbedaan, persamaan keduanya adalah menggunakan logika cost‐
benefit dalam setiap kalkulasi tindakan manusis. Prilaku manusia, akhirnya ditentukan
dari perhitungan‐perhitungan rasional yang ia refleksikan sebelum mengambil
keputusan. Problem dari pendekatan seperti ini adalah bahwa ia begitu saja menerima
secara taken for granted tentang corak tertentu dari rasionalitas. Mengapa yang dianggap
rasional adalah yang demikian (as such) dan bukan lainnya? Proses‐proses apa yang
menjadikan gagasan rasionalitas menjadi bercorak yang demikian? Pertanyaan‐
pertanyaan ini jelas tidak akan mampu di jawab pendekatan ini. Kerja teoritik mereka
berada di dalam satu bentuk rasionalitas, sehingga klaim‐klaim teoritis yang mereka
hasilkan hanya berlaku sepanjang rasionalitas yang dipakai pendekatan ini secara taken
for granted tidak berubah.
Berikutnya pendekatan psikologis. Teori yang umumnya digunakan, misalnya,
teori hirarki kebutuhan Abraham Maslow. Teori ini begitu terkenalnya sehingga ia terus
dimodifikasi dan diperbarui. Sekalipun demikian, asumsi dasarnya tetap tidak tersentuh.
Secara umum, teori ini mencoba memeringkatkan kebutuhan manusia secara berurutan:
biologis (makan, minum, tidur, seks), keamanan (tatanan, hukum), afeksi (belongingness,
cinta, kasih‐sayang), penghargaan (esteem, capaian, status), aktualisasi‐diri (tujuan
hidup). Perkembangan terbaru mencoba menambahkan kebutuhan kognitif
(pengetahuan, kesadaran) dan estetis (keindahan, keseimbangan) sebelum kebutuhan
aktualisasi‐diri, dan kebutuhan transenden (menolong, berderma) setelah kebutuhan
aktualisasi‐diri.
Problem dari pendekatan ini ada di seputar pertanyaan mengenai asal‐usul dari
masing‐masing bentuk dari needs itu sendiri. Segala bentuk obyek kebutuhan dalam
setiap tangga hirarki ini diasumsikan terberi begitu saja. Semisal, kebutuhan estetis, tidak
pernah dipertanyakan mengapa konsepsi keindahan yang demikian yang dianggap
estetis dan bukan versi lainnya. Begitu pula dengan kebutuhan akan kemanan, jarang
tepikirkan untuk menginterogasi mengapa seseorang merasa aman dalam sistem
keamanan demikian dan bukan lainnya. Hal ini, belum lagi melihat unsur‐unsur sosial‐
9
politis yang membentuk bentuk gagasan keindahan dan keamanan tadi. Di sini
pendekatan psikologis menemui keterbatasannya.
Untuk menambal keterbatasan ini, studi ini akan menggunakan pendekatan
psikoanalisis yang digagas dan dikembangkan oleh Jacques Lacan dan para penerus
tradisinya, seperti, terutama, Slavoj Zizek dan Jodi Dean. Psikoanalisis melihat seluruh
prilaku manusia sebagai sesuatu yang memiliki asal‐usul libidinal, yaitu hasrat. Adalah
hasrat yang menjadi motor seseorang untuk berhasrat. Hal ini akan menjadikan piramida
Maslowian menjadi sama sekali bermasalah dan tidak relevan. Misalnya, paling
sederhana: mengapa manusia makan? Maslow dan pengikutnya akan menjawab bahwa
itu adalah kebutuhan biologis. Tapi bagaimana dengan misalnya, para petapa, atau para
pemogok makan? Mereka tidak makan demi mendapat estetika (pertapa) dan rekoginisi
(pemogok). Artinya, dalam horizon Maslowian, mereka “melompati” hirarki kebutuhan
tersebut. Dan ini adalah sesuatu yang tidak terjelaskan bagi pendekatan Maslowian.
Dorongan hasrat dan obyek hasrat
Sehingga penting di sini untuk membedah prilaku manusia. Dengan
menggunakan psikoanalisis Lacanian, prilaku harus selalu dilihat sebagai sesuatu yang
selalu merupakan efek dari suatu dorongan (drive)21 hasrat. Dorongan ini bersifat
primordial dan sifatnya inheren. Semenjak manusia lahir, ia sudah memiliki dorongan.
Hanya saja, ia belum memiliki saluran dan muara untuk mengarahkan dorongan hasrat
tersebut. Di sinilah pentingnya melihat aspek lain dari hasrat, yaitu obyek hasrat. Obyek
hasrat merupakan muara dari dorongan tersebut. Jadi, kembali ke contoh makan,
‘dorongan untuk memuaskan rasa lapar’ (libidinal) adalah berbeda dan lebih dalam dari
sekedar ‘memuaskan rasa lapar’ (biologis) itu sendiri. Yang pertama ini punya motivasi
yang tidak sekedar memuaskan rasa lapar, melainkan untuk memuaskan hasrat untuk
bertahan hidup. Hasrat bertahan hidup ini, sebenarnya hanyalah satu macam hasrat saja;
masih ada bentuk hasrat lainnya.
Melalui contoh ini, dapat dilihat bagaimana obyek hasrat hasrat harus dilihat
setidaknya sebagai dua lapis: identitas dan obyek.22 ‘Identitas hasrat’ merupakan motivasi
libidinal/hasrati sang subyek untuk menghasrati obyek hasrat yang mengandung
identitas hasrat tersebut.23 Obyek inilah yang disebut Lacan sebagai ‘obyek penyebab
hasrat’ (object cause of desire). Jadi, anatomi hasrat dapat dibedah ke dalam dua aspek:
identitas hasrat dan obyek hasrat. Dalam setiap obyek hasrat, dengan demikian, selalu
21 Kesalah‐kaprahan fatal dalam terjemahan Indonesia adalah dengan menerjemahkan konsep ini ke ‘insting’.
Insting lebih condong ke arah intuisi; sementara dorongan lebih menekankan dimensi ketidak‐sadaran yang
sifatnya memaksa, yang lebih cocok dalam pandangan Lacan sendiri. 22 Sebenarnya ada tiga, dengan yang ketiga disebut Lacan sebagai ‘the real of the desire’, atau di lain
kesempatan, ‘lamela’. Namun, untuk kepentingan studi ini, dua saja sekiranya cukup untuk menjelaskan. Untuk
catatan ini, lihat Jacques Lacan, The Seminar of jacques Lacan, Book XI: The Four Fundamental Concept of Psychoanalysis,
terj. A. Sheridan (London, NY: W.W.Norton & Company, 1981), hlm. 98. 23 Lacan tidak mengutarakan konsep ‘identitas hasrat’ ini. Untuk gagasan yang diacu konsep ini, Lacan
menggunakan konsep ‘obyek a’ (objet petit a). Demi kepentingan penyederhanaan dan meminimalisir terlalu
banyak konsep teknis yang jarang digunakan, maka kami memilih menggunakan ‘identitas hasrat’ yang lebih
“ramah di telinga.”
10
tersimpan identitas‐identitas hasrat. Namun demikian yang penting ditekankan adalah
bahwa identitas hasrat sebenarnya tidak pernah tersimpan begitu saja dalam obyek
hasrat; identitas hasrat dalam obyek hasrat adalah selalu merupakan hasil proyeksi dan investasi
dorongan hasrat sang subyek. Artinya, identitas hasrat sebenarnya tidak pernah ada dalam
obyek tersebut dengan sendirinya; adalah subyek yang memproyeksikan hasratnya ke
obyek tersebut sehingga seolah‐olah obyek tersebut memendam suatu harta karun hasrati
tertentu.
Di sini, mau tidak mau, analisis harus mempertimbangkan aspek sosial politik
yang berupaya mengarahkan, mengkanalisasi, mengorientasi, dan menggiring dorongan hasrat
ke arah obyek hasrat tertentu yang notabene telah terlebih dahulu dikonstruksikan makna dan
nilai pemuasan hasratnya. Memahami proses penggiringan ini, maka penting untuk juga
menjelaskan proses ‘identifikasi’ identitas hasrat dalam obyek‐obyek hasrat. Hal ini
demikian karena semenjak obyek hasrat dihasrati karena (dikira subyek) memiliki
identitas‐identitas hasrat tertentu, maka proses identifikasi ini juga berpotensi menjadi
medan kontestasi sosial politik. Artinya, obyek hasrat itu sendiri tidak pernah natural; ia
selalu merupakan produk kontestasi sosio‐potis yang bersifat historis di zamannya
masing‐masing. Seperti kata Zizek,
“The problem for us is not ‘are our desire satisfied or not’. The problem is ‘how do we know what
we desire?’ There is nothing spontaneous, nothing natural about human desires. Our desires are
artificial. We have to be taught to desire.”24
Aspek sosial politik di sini menjadi tidak terelakkan karena dalam dorongan hasrat,
terkandung suatu energi. Energi yang menggerakan sang subyek untuk menjawab
dorongan hasratnya. Adalah energi ini yang apabila dikonsentrasikan dan dikumpulkan,
bisa dieksploitasi dan dimanfaatkan oleh siapa saja. Kontrol terhadap hasrat di level
identifikasi hasrat ini akhirnya akan menganugerahi seseorang dengan kekuasaan
(power), yaitu kekuasaan libidinal (libidinal power).
Tipologi Identitas Hasrat Lacanian
Demi kepentingan sistematisasi studi, maka penting untuk menerjemahkan
konsep ‘identitas hasrat’ ini ke bentuk yang lebih operasional. Untuk ini, studi ini
mengikuti jejak yang dibuka oleh Mark Bracher.25 Pintu masuk Bracher untuk
operasionalisasi ini adalah definisi tersohor dari Lacan sendiri tentang hasrat, yaitu
bahwa hasrat adalah selalu “hasrat akan yang lain’ (“desire finds its meaning in the desire of
the other”)26. Kalimat “hasrat akan ‘yang lain’” ini mengandung tiga ambiguitas.
Ambiguitas ini menunjuk pada tiga landasan pembedaan hasrat. Landasan pertama, kata
“hasrat” bisa merupakan hasrat untuk menjadi dan bisa juga hasrat untuk memiliki.
24 Kalimat ini diteruskan dengan, “cinema is the ultimate pervert art. It doesnt give you what you desire. It tells you
how to desire.” Slavoj Žižek, The Pervert’s Guide to Cinema: Lacanian Psychoanalysis and Film, (London: Mount Pleasant
Studios, 2006). [Film Dokumenter] 25 Mark Bracher, Lacan, Discourse, and Social Change: A Psychoanalytic Cultural Criticism (Ithaca & London:
Cornell Uni Press, 1993), bab 1. 26 Jacques Lacan, Écrits: A selection, terj. A. Sheridan (London: Tavistock, 1977 [1966]), hlm. 43.
11
Pembedaan ini sesuai dengan pembedaan libido narsistik dan libido anaklitik oleh Freud.27
Kedua, kata “akan,” menunjukan bahwa subjek hasrat tersebut bisa menjadi subjek aktif
(yang meng‐hasrati) dan objek pasif (yang di‐hasrati). Terakhir, kata “yang lain” inilah yang
merupakan identitas hasrat. Mengacu ke penjelasan Lacan, identitas hasrat terposisikan
di dalam tiga ranah (register) yang saling bertalian, yaitu: ranah Imajiner, yang
memanifestasi ke dalam citra‐ideal (ideal image); ranah Simbolik, yang memanifestasi
pada tanda; dan ranah Riil yang memanifestasi dalam bentuk fantasi.
(Secara singkat, ketiga ranah ini dapat dijelaskan sebagai berikut: ranah Imajiner
berkaitan dengan suatu konsepsi ideal yang abstrak; ia juga merupakan suatu bentuk
kesatuan, keutuhan, integralitas, yang dengan demikian, juga dengan dengan jelas
menarik garis batasan antara saya/liyan, ideal/buruk, tapi juga hitam/putih, pantas/tidak,
dst. Hasrat yang berada di ranah Simbolik akan selalu terreduksi (bahasa Lacan,
terkastrasi) ke dalam bentuk‐bentuk yang kongkrit; bentuk‐bentuk ideal dalam ranah
Imajiner tadi mendapat bentuk kongkritnya dalam rupa‐rupa simbolisasi, penamaan,
pelabelan, dst., yang merupakan ciri khas ranah Simbolik. Ranah Riil, merupakan ekses
dari kedua ranah sebelumnya. Ciri utamanya adalah bahwa ia selalu merupakan
sebentuk kemustahilan. Saat hasrat yang ideal dari ranah Imajiner diterjemahkan ke
dalam ranah Simbolik, maka akan selalu ada yang hilang dalam translasi itu (lost in
translation). Akibatnya, hasrat tidak akan pernah utuh, final, paripurna dan bulat.
Pemenuhan suatu hasrat, hanya akan membawa sang subyek untuk memenuhi hasrat
lainnya, dan demikian seterusnya sampai ia mati dalam proses pemenuhan hasrat itu
sendiri. Adalah yang Riil ini yang membuat hasrat menjadi sebuah kemustahilan, dengan
demikian, mengkonfirmasi anggapan umum mengenai hasrat sebagai jurang tak
bertepi.)28
Sampai sini dapat disimpulkan terdapat total 12 jenis identitas hasrat yang
memotivasi prilaku‐prilaku manusia sehari‐hari, dengan empat jenis hasrat yang
memanifestasi di masing‐masing ranah (citra‐ideal, tanda, fantasi): hasrat Narsistik Pasif
yaitu hasrat untuk menjadi objek cinta “yang lain;” hasrat Narsistik Aktif, yaitu hasrat
untuk menjadi “yang lain” lewat identifikasi; hasrat Anaklitik Aktif, yaitu hasrat untuk
memiliki “yang lain” sebagai objek pemuas; dan hasrat Anaklitik Pasif, yaitu hasrat untuk
dimiliki “yang lain” sebagai objek pemuasnya. Ke‐12 tipologinya dapat ditabulasikan
sebagai berikut: (untuk uraian lebih ekstensif, telampir)
Identitas
Hasrat
Narsistik Anaklitik
Aktif Pasif Aktif Pasif
27 Narsis diadopsi dari Narcissus, tokoh Yunani kuno yang cinta dirinya sendiri. Oleh karena itu, libido
narsistik adalah libido yang mengarah pada Ego, menjadi suatu citra‐diri Ego. Anaklitik berasala dari kata Yunani,
Anaklitos, yang artinya bersandar. Dengan demikian, libido anaklitik adalah libido yang menyandarkan
kepuasannya pada kepemilikan suatu objek. Sigmund Freud, The Standard Edition of the Complete Psychological
Works of Sigmund Freud, vol. 14 (London: Hogarth Press, 1953‐7), hlm. 76‐89. 28 Disarikan secara umum dari, Jacques Lacan, The Seminar of Jacques Lacan, Book XXII, 1974‐75, peny. J‐A.
Miller, terj. J.W.Stone dari transkrip milik Editions Du Seuil. [Naskah tidak terbit].
12
Imajiner Narsistik Aktif
Imajiner
Narsistik Pasif
Imajiner
Anaklitik Aktif
Imajiner
Anaklitik Pasif
Imajiner
Simbolik Narsistik Aktif
Simbolik
Narsistik Pasif
Simbolik
Anaklitik Aktif
Simbolik
Anaklitik Pasif
Simbolik
Riil Narsistik Aktif
Riil
Narsistik Pasif
Riil
Anaklitik Aktif
Riil
Anaklitik Pasif
Riil
Tabel 1 Tipologi Identitas Hasrat dalam Psikoanalisis Lacanian
Simtom: Modus Artikulasi Dorongan Hasrat (dalam Wacana)
Hal lain yang juga perlu dibahas adalah terkait aktualisasi upaya‐upaya untuk
mewujudkan hasrat tersebut. Di sini kita berbicara mengenai modus‐modus artikulasi
dorongan hasrat, atau yang disebut Lacan sebagai ‘simtom’ (symptom). Simtom adalah
segala sesuatu, sekali lagi, segala sesuatu yang dilakukan dan ditampakkan oleh sang
subyek hasrat, baik itu (dikira) disadari maupun tidak. Simtom ini merupakan titik
pertemuan antara subyek dengan obyek hasrat berikut ke‐12 identitas yang sudah di
bahas di atas. Ada berbagai macam simtom tentunya: mulai dari makan, berpikir,
berolahraga, beribadah, bahkan sampai berpolitik, berkarir, tapi juga marah, sedih, dst.
Namun demikian, tidak semua akan dipakai dalam studi ini. Hanya simtom yang merupa
dalam wacana saja yang akan dipakai dalam studi ini. Pun dalam studi ini, wacana
tersebut juga terpaksa direduksikan lagi ke dalam sebarisan kata‐kata yang diungkapkan
seseorang dalam rangka mewujudkan partisipasinya dalam proses demokrasi.29
Secara umum, mengikuti Lacan, wacana simtomatik selalu mengasumsikan dua
jenis posisi—‘pengidentifikasi’ dan ‘yang‐diidentifikasi’—dan dua jenis dunia30—tampak
dan tak sadar.31 Skemanya dapat dilihat sebagai berikut:
* Keterangan:
29 Tentang betapa kayanya praktik‐praktik yang terkandung dalam ‘wacana’, lihat Sara Mills, Discourse
(London, NY: Routledge, 2004). 30 Dunia di sini diartikan sebagai sekumpulan dan/atau jejaring pemaknaan. 31 Jacques Lacan, The Seminar of Jacques Lacan. Book XVII. The Other Side of Psychoanalysis, peny. J.‐A. Miller,
terj. R. Grigg (NY, London: W.W. Norton & Company, 2007)
Skema 1. Susunan Skema Simtom‐Wacana
Pembicara Penerima
Pelaku ”yang lain” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Kebenaran Produksi
13
Ruas kiri, adalah yang posisi yang aktif berbicara atau mengirimkan pesan; sedangkan yang berada
di ruas kanan adalah faktor‐faktor yang diaktifkan atau yang muncul dari subyek saat ia
menerima pesan.
Ruas atas, merupakan faktor‐faktor yang tampil / kelihatan; sementara ruas bawah merupakan
faktor yang tersembunyi, implisit, bahkan terepresi.
Ruas kiri atas, ditempati oleh pelaku yang aktif mendominasi; ruas kiri bawah, merupakan faktor
yang mendorong, mendukung, dan melandasi bangkitnya faktor dominan, tetapi tertekan
olehnya; kanan atas, merupakan faktor yang diaktifkan (jadi, tidak pasif) sebagai prasyarat
menerima / memahami pesan (contoh, bersikap reseptif dan mengosongkan diri untuk
sementara); kanan bawah, merupakan faktor yang diharapkan saat penerima telah menerima
dan memahami pesan, yaitu mengartikulasikannya.
Keempat ruas tersebut akan ditempati secara silih berganti oleh empat komponen
(berikut notasinya): otoritas Simbolik/sistem universal (S2), citraan Imajiner/ego‐ideal
(S1), hasrat tak sadar/objek a (a), dan subjek gegar ($) yang terbelah di antara tarik‐menarik
Imajiner–Simbolik dengan pemuasan objek a. Karena ego‐ideal selalu mensyaratkan
abyeksi,32 maka susunan komponen tersebut penulis tambahi dengan abjek (S0)—“0”
untuk melambangkan ketiadaan. Interaksi di antara kelimanya adalah sebagai berikut:
suatu wacana yang komplit akan menyiratkan suatu gagasan universal. Gagasan
universal ini akan memproduksi suatu ego yang ideal dengan cara memberikan kriteria
subjek dan abjek. Ego ideal ini dimaksudkan untuk menambal kegegaran subjek itu
sendiri, dan orang lain jika itu diarahkan ke luar dirinya. Penambalan ini akan
memberikan kepuasan tersendiri bagi subjek.
Komposisi keseluruhan komponen ini akan membentuk, setidaknya, empat
macam struktur artikulasi simtom: Diskursus Universitas (University Discourse), yang
mempengaruhi dengan cara mendidik / mengindoktrinasi melalui pengetahuan;
Diskursus Penguasa (Master’s Discourse) yang mempengaruhi dengan cara mengatur /
memberi perintah melalui idealisme; Diskursus Histeris (Hysterical Discourse) yang
mempengaruhi dengan cara menghasrati / memprotes melalui pembagian diri (gegar);
Diskursus Sang Analis (Analyst’s Discourse) yang mempengaruhi dengan cara menganalisis
/ mentransformasikan / merevolusikan melalui rasa sukacita. (Untuk uraian lebih ekstensif,
telampir).
Studi ini menggunakan data primer berupa “kicauan” (tweet) para pengguna
mikro‐blog Twitter, dengan kata kunci ‘pilkada’ dan ‘pilgub’. Data diambil selama
hampir dua minggu; mulai Rabu, 12 September 2012, hingga Senin, 24 September 2012.
Periode tersebut sengaja dipilih dengan mempertimbangkan besarnya minat masyarakat,
khususnya para pengguna Twitter, beberapa hari menjelang dan setelah pemilihan
gubernur DKI Jakarta dilaksanakan (Kamis, 20 September 2012). Dengan banyaknya tweet
yang terekam, maka Peneliti kemudian menetapkan protokol seleksi terhadap seluruh
32 Subyeksi merupakan proses yang melaluinya seonggok tubuh yang disebut ‘manusia’ menjadi subyek.
Melalui subyeksi, manusia dipakaikan suatu identitas yang menentukan siapa dia (subyek) dan siapa yang bukan
dia (abyek). Abyeksi adalah proses yang melaluinya sang subyek mengidentifikasi, dan kemudian menyingkirkan
aspek‐aspek yang mengganggu keutuhan ideal imajiner subyektivitasnya. Abyeksi, dengan demikian adalah
proses yang selalu mengikuti proses subyeksi. Untuk catatan ini, lihat Judith Butler, Bodies thatMatter (London,
NY: Routledge, 1993), bab 1.
14
tweet yang telah dikumpulkan agar mempermudah proses analisis. Protokol tersebut
adalah sebagai berikut:
Topik yang “dikicaukan” adalah seputar pilkada/pilgub DKI Jakarta dan
bukan di daerah lain.
Kicauan atau tweet bukan merupakan berita/informasi, serta bukan
pengulangan atau retweet dari berita/informasi.
Meski menggunakan kata kunci ‘pilkada’ atau ‘pilgub’, topik yang disinggung
oleh para pengguna Twitter dapat berbeda‐beda namun masih seputar
pilkada/pilgub DKI Jakarta. Untuk itu, Peneliti membagi topik kicauan lebih
detil ke dalam lima hal terkait pilkada/pilgub DKI Jakarta, yakni: event
pilkada/pilgub itu sendiri, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur
dalam pilkada putaran kedua, rakyat/Jakarta/Indonesia, demokrasi, serta lain‐
lain yang tidak termasuk ke dalam empat hal sebelumnya.
Setiap pengulangan dari tweet (retweet, RT) yang lolos protokol seleksi di atas
akan dihitung sebagai satu data.
Data yang dicari berjumlah total 1.000 (seribu) data tweets siap analisis, dengan
rincian 500 (lima ratus) tweets berkata kunci ‘pilkada’ dan 500 (lima ratus)
tweets berkata kunci ‘pilgub’.
Sebaran Obyek Hasrat
Dari 1000 (seribu) data tweets yang terkumpul, baik dengan kata kunci ‘pilkada’
maupun ‘pilgub’, objek hasrat yang nampak dominan adalah pemilihan kepala daerah
(pilkada) atau pemilihan gubernur (pilgub) DKI Jakarta 2012 itu sendiri, yakni sebanyak
521 tweets. Para pengguna Twitter “mengicaukan” berbagai hal terkait penyelenggaraan
event ini seperti prosedur pelaksanaan pilkada/pilgub yang ideal, mengomentari strategi
kampanye yang digunakan oleh kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur
selama masa kampanye, hingga perihal keterkaitan antara pilkada/pilgub DKI Jakarta
2012 dan pemilihan presiden pada 2014. Di antara komentar‐komentar atas
penyelenggaraan pilkada/pilgub yang ideal tersebut, suara “kicauan” yang paling
menonjol berupa keprihatinan masyarakat pengguna Twitter akan isu SARA (Suku,
Agama, Ras, dan Antargolongan) yang beredar selama pilkada/pilgub ini. Mulai dari
suara‐suara yang menanggapi isu ini dengan nada bercanda (menyindir) hingga yang
mengkritik keras muatan‐muatan SARA selama proses pilkada/pilgub ini berlangsung.
Meski demikian, ada pula tweets yang, sebaliknya, justru mendukung pelibatan isu SARA
sebagai bahan pertimbangan dalam memilih gubernur‐wakil gubernur DKI Jakarta
putaran kedua.
15
Objek hasrat kedua dominan seperti dalam grafik di atas adalah kedua pasangan
calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) peserta pilkada/pilgub DKI
Jakarta 2012, yakni sejumlah 195 tweets. Umumnya, Twitter digunakan oleh para
pendukung kedua pasangan untuk mendukung calon pilihannya, dengan atau tanpa
menyebutkan alasan optimisme mereka terhadap pasangan cagub dan cawagub tersebut.
Selain itu, tidak sedikit pula tweets yang ditujukan kepada salah satu pasangan dan berisi
kritikan atau sindiran terhadap mereka. Sedangkan pola lain yang ditemukan adalah
suara‐suara yang menginginkan adanya calon independen dalam pilkada/pilgub DKI
Jakarta 2012; oleh karena adanya ketidakpuasan para tweeps33 tersebut atas kedua
33 Sebutan bagi para pengguna Twitter.
Pilkada/Pilgub52%
Pasangan19%
Rakyat/Jakarta/Indonesia10%
Demokrasi9%
Lainnya10%
Sebaran Obyek Hasrat
521
195
97 91 96
Sebaran Obyek Hasrat
16
pasangan cagub‐cawagub peserta pilkada/pilgub DKI Jakarta yang lolos ke putaran
kedua. Namun, pola yang terakhir sangat minim jumlahnya dibandingkan dengan
kicauan berbentuk dukungan bagi salah satu dari kedua pasangan cagub‐cawagub
peserta pilkada/pilgub DKI Jakarta 2012 yang lalu.
Objek hasrat yang umum ditemukan ketiga adalah rakyat/Jakarta/Indonesia,
dengan jumlah 97 tweets. Tweets yang masuk dalam kategori ini juga memperlihatkan
bagaimana masyarakat pengguna Twitter sering menggunakan Jakarta sebagai
pembanding atas kondisi politik domestik Indonesia. Banyak tweets yang berisi harapan
dan keinginan atas terwujudnya rakyat/Jakarta/Indonesia “yang lebih baik” melalui event
pilkada/pilgub DKI Jakarta yang lalu. Terwujudnya “rakyat yang lebih baik” seperti
misalnya harapan untuk masyarakat Jakarta (dan ada pula tweets yang merujuk kepada
masyarakat Indonesia, seperti tweet berikut: Another drama, ketakutan tnp dasar, ayooo dong
Indonesia, move onʺ@sutomoagus92: Hanya soal pilgub aja, seolah2 akan terjd tragedi thd bgs)
agar menjadi semakin kritis dan “dewasa” dalam berdemokrasi, khususnya dalam
memilih pemimpin melalui pemilihan umum. Sedangkan harapan atas “Jakarta yang
lebih baik” tampak lebih variatif: mulai dari yang praktis—Jakarta bebas macet,
misalnya—hingga yang abstrak—sebagian besar adalah tentang Jakarta yang “berubah”.
Sementara mengenai “Indonesia yang lebih baik”, suara‐suara yang cenderung muncul
adalah harapan mengenai Indonesia yang damai dan plural (terkait beredarnya isu SARA
dalam pilkada/pilgub DKI Jakarta 2012).
Tidak jauh berbeda dalam jumlah, objek hasrat keempat yang umum muncul dari
data yang terkumpul adalah ‘lainnya’, yaitu sebanyak 96 tweets. Objek hasrat dalam
kelompok ini sangat variatif; seperti misalnya media televisi, lembaga survey, agama,
jingle kampanye, calon independen, partai, dan lain‐lain yang kesemuanya masih
berkaitan dengan proses berlangsungnya event pilkada/pilgub DKI Jakarta yang lalu. Di
antara objek‐objek hasrat yang masuk ke dalam kelompok ‘lainnya’ ini, objek hasrat yang
cukup menonjol dan sering dibicarakan adalah media televisi. Kicauan yang terkumpul
banyak menyoroti bagaimana media (seharusnya) berperan dalam menyosialisasikan
event tersebut secara ideal, salah satunya misalkan tidak timpang memberitakan event
lokal yang satu dengan yang lain, sehingga isu lokal seperti pilkada DKI Jakarta tiba‐tiba
menjadi event nasional.
Objek hasrat terakhir yang nampak dalam analisis ini adalah ‘demokrasi’, dengan
jumlah 91 tweets. Demokrasi yang dimaksud dalam tweets pada kelompok ini adalah
suara rakyat yang tercermin dalam pemilihan umum/pilkada/pilgub. Tweets dengan
objek hasrat ‘demokrasi’ inipun ada yang bernada menyindir proses demokrasi
(pilkada/pilgub dan juga pemilihan presiden) di Indonesia yang tidak jujur, tetapi juga
ada yang berupa himbauan ataupun harapan untuk mendukung proses demokrasi
tersebut agar dapat berjalan semakin baik.
Sebaran Motivasi Hasrat
Sedangkan dari kategori motif hasratnya, pada 1000 data tweets yang terkumpul
cenderung didominasi oleh kategori hasrat Aktif‐Anaklitik‐Simbolik dengan jumlah 500
17
tweets dan Aktif‐Anaklitik‐Imajiner dengan jumlah 347 tweets. Ini berarti, pada umumnya
masyarakat pengguna Twitter itulah yang secara aktif mengambil inisiatif untuk
menghasrati objek hasrat yang terdapat dalam tweets mereka masing‐masing untuk
pemuasan hasrat diri mereka sendiri. Hasrat tersebut umumnya adalah hasrat untuk
memiliki sesuatu yang bersifat simbolik/konkret. Masyarakat cenderung memerhatikan
dan karenanya merefleksikan apa yang mereka amati dari lingkungan mereka untuk
kemudian menghasrati sesuatu yang bersifat simbolik/konkret terkait pilkada; hal‐hal
seperti misalnya terkait prosedur pelaksanaan pilkada/pilgub, ada‐tidaknya isu SARA
dalam kampanye, metode berkampanye yang sportif, dll. Contohnya, tweet yang
mengkritik strategi kampanye yang digunakan oleh salah satu pasangan peserta putaran
kedua pilkada/pilgub DKI Jakarta 2012, yang memakai lagu religi berikut ini:
Iya, lagu religi itu ga pas banget, intimidatif RT @imanbr: Sayup sayup suara TV, kupikir iklan
Ramadhan. Eh taunya iklan pilkada :)).
Sedangkan pada jumlah kedua terbanyak, motif hasrat yang muncul dalam data
tweets yang terkumpul adalah Aktif‐Anaklitik‐Imajiner. Hampir sama dengan motif
hasrat yang dominan pertama sebelumnya, hanya saja kali ini apa yang diinginkan untuk
dimiliki oleh para tweeps tersebut bersifat imajiner/abstrak, seperti misalnya Jakarta “yang
lebih baik”, Indonesia “yang lebih dewasa dalam berdemokrasi”, ataupun pemimpin
“yang mampu mengatasi berbagai masalah di Jakarta/Indonesia”. Kecenderungan ini
menampilkan ide‐ide masyarakat pengguna Twitter tentang masyarakat, Jakarta,
Indonesia, dan objek hasrat lainnya yang ideal terkait event pilkada/pilgub atau bahkan
pemilihan umum di tingkat nasional sekalipun. Bentuknya dapat berupa sindiran atas
kondisi rakyat/Jakarta/Indonesia yang tidak ideal ataupun pujian dan himbauan untuk
menuju rakyat/Jakarta/Indonesia yang ideal.
2%3%
0%
35%
50%
0%1%
0%0%
6%
3%
0%
Sebaran Motif Hasrat
Aktif‐Narsistik‐Imajiner
Aktif‐Narsistik‐Simbolik
Aktif‐Narsistik‐Real
Aktif‐Anaklitik‐Imajiner
Aktif‐Anaklitik‐Simbolik
Aktif‐Anaklitik‐Real
Pasif‐Narsistik‐Imajiner
Pasif‐Narsistik‐Simbolik
Pasif‐Narsistik‐Real
Pasif‐Anaklitik‐Imajiner
Pasif‐Anaklitik‐Simbolik
18
Motif hasrat ketiga yang umum ditemukan dalam data studi ini adalah Pasif‐
Anaklitik‐Imajiner sebanyak 59 tweets. Motif hasrat ini sama dengan motif hasrat
sebelumnya; namun berbeda dalam hal tujuan pemenuhan hasratnya. Kategori hasrat
yang ‘pasif’ dapat dikenali dari tujuan pemenuhan kepuasan/hasratnya yang bukan diri
sendiri (para pengujar tweets tersebut), melainkan sesuatu di luar diri mereka. Misalnya
seperti dalam tweet berikut, yang nampak jelas bahwa tujuan pemenuhan hasratnya
adalah untuk “kemenangan rakyat, untuk demokrasi, untuk nusantara jaya”:
Meski bkn warga dki,tp mengikuti perkembangan pilgub dki sgt mendebarkan,dan inilah
kemenangan rakyat,untuk demokrasi,utk nusantara jaya.
Motif hasrat berikutnya yang juga cukup banyak muncul adalah Aktif‐Narsistik‐
Simbolik sebanyak 32 tweets, Pasif‐Anaklitik‐Simbolik sebanyak 31 tweets, dan Aktif‐
Narsistik‐Imajiner sebanyak 23 tweets. Motif narsistik dikenali dari hasrat untuk menjadi
sesuatu, bukan memiliki; baik yang bersifat konkret (simbolik) dan abstrak (imajiner).
Contoh tweet dengan motif Aktif‐Narsistik‐Simbolik yang ditemukan dalam data adalah
seperti berikut ini: Beberapa minggu ke blk ini isu agama lagi mencuat2nya. Entah itu saat
penangkapan teroris atau pilgub DKI. Personally, I choose secularism. Dengan menekankan
pilihan pribadi di akhir tweet‐nya, pengguna Twitter tersebut ingin masyarakat, termasuk
ia di dalamnya agar menjadi sekuler, terkait isu agama yang beredar di publik saat itu
(bener ga Mas?). Motif hasrat lain yang ditemukan adalah Pasif‐Narsistik‐Imajiner
sebanyak 5 tweets, Aktif‐Anaklitik‐Real sebanyak 2 tweets dan Pasif‐Narsistik‐Simbolik
sebanyak 1 tweets. Temuan data ini menunjukkan hanya sedikit sekali tweets yang masuk
ke dalam kategori motivasi hasrat Real atau yang tidak terjelaskan.
Sebaran Struktur Wacana Hasrat
23 320
347
500
2 5 1 0
5931
0
Sebaran Motif Hasrat
19
Seluruh hasrat itu umumnya disampaikan dalam bentuk Hysteric Discourse, yakni
sebanyak 402 tweets; University Discourse, sebanyak 308 tweets; Master Discourse sebanyak
267 tweets; dan dalam bentuk Analyst Discourse sebanyak 23 tweets. Para tweeps yang
menyampaikan hasratnya dalam bentuk hysteric discourse umumnya menyindir,
memprotes, dan mengkritik objek hasrat mereka seperti misalnya pasangan cagub‐
cawagub yang tidak sportif dalam mengikuti prosedur pilkada/pilgub, media yang tidak
suportif terhadap pelaksanaan pilkada yang ideal, partai politik yang tidak ideal, dan
lain‐lain. Sedangkan University Discourse umumnya digunakan oleh para tweeps untuk
mendukung atau memuji objek hasrat mereka, baik itu event pilkada/pilgub DKI Jakarta
yang lalu, salah satu pasangan atau kedua pasangan cagub‐cawagub peserta
pilkada/pilgub DKI Jakarta, rakyat yang sudah semakin awas dengan mekanisme
pilkada/pilgub, dan lain‐lain.
Sementara itu, Master Discourse cenderung dipakai untuk mengomentari objek
hasrat dalam tweet dan dengan diikuti sanggahan atau dukungan dari si pengguna
Twitter mengenai objek hasrat tersebut, misalnya mengenai kelompok golongan putih
(golput), pasangan cagub‐cawagub tertentu, atau tentang praktik demokrasi seperti yang
nampak dalam salah satu tweet yang banyak di‐retweet ini:
Inilah Demokrasi. Calm :)“@ibutjantik: Kyknya blm prnh senorak & spanik bgini ya.
ʺ@RosiSilalahi: Ini TL makin panas aja soal PilkadaDKI.ʺ”
Terakhir, struktur yang paling sedikit ditemukan adalah struktur Analyst Discourse
di antara data tweets yang terkumpul. Di antara mereka yang memakai struktur Analyst
Discourse ini, yang paling banyak ditemukan adalah para tweeps yang berasal dari
kelompok pelajar, yang tidak atau belum menjadi pemilih dalam pemilihan umum.
Sehingga komentar mereka pada umumnya adalah tidak peduli dengan berlangsungnya
event maupun hasil dari pilkada/pilgub DKI Jakarta. Selain itu, ada pula anggota
masyarakat yang apatis dengan praktik politik di Indonesia, mereka yang tidak dapat
University Discourse
31%
Master Discourse
27%
Hysteric Discourse
40%
Analyst Discourse
2%
Sebaran Struktur Wacana
20
mengikuti pilkada/pilgub karena berasal dari luar Jakarta, atau mereka yang tidak
menggunakan hak pilihnya karena alasan tertentu (yang disebutkan juga dalam tweet).
Akan tetapi, yang menarik ialah jika pemakai struktur Analyst Discourse kebanyakan
adalah mereka yang memang pesimis dengan hasil pilkada/pilgub/pemilihan umum;
namun demikian ada pula pengguna Twitter yang menggunakan struktur Analyst
Discourse untuk menyampaikan hasrat mereka untuk terlibat aktif dalam pilkada/pilgub
DKI Jakarta seperti tweet berikut “Bosen juga tiap pilgub yg dicoblos semua photo alias
golput, kali ini harus milih #pilgub.”
21
Bagian berikutnya merupakan upaya penulis untuk menarik implikasi dari pola‐
pola dominan yang ditemukan dalam studi. Temuan‐temuan ini akan didiskusikan
dengan mengaitkannya pada konsep dan praktik partisipasi demokrasi itu sendiri. Pula
pada bagian ini akan coba ditunjukkan kenyataan psikoanalitik mengenai partisipasi
demokrasi, yaitu bahwa partisipasi tersebut tidak pernah diarahkan untuk partisipasi itu
sendiri, melainkan ia selalu ditujukan untuk tujuan yang eksternal dari partisipasi, yaitu
hasrat‐hasrat pribadi sang subyek. Bab ini akan mendiskusikan pandangan dan teori
dominan mengenai partisipasi demokrasi. Lalu pandangan tersebut akan ditunjukkan
beberapa keterbatasannya. Barulah temuan‐temuan dalam studi ini dibawa untuk
dipertimbangkan dalam perdebatan mengenai partisipasi demokrasi tersebut.
Partisipasi Demokarsi: Deliberatif?
Dalam salah satu tulisannya, Jurgen Habermas mengungkapkan bahwa
komunikasi politik dalam ranah publik dapat memfasilitasi proses legitimasi yang
deliberatif hanya apabila sistem media memperoleh kebebasan dari lingkungan
sosialnya, dan apabila para penyimak mendapatkan feedback dalam dialog antara para
elit dan masyarakat sipil yang responsif. Selanjutnya, terdapat tiga elemen penting dalam
demokrasi modern, yakni kebebasan dan kesetaraan masyarakat dalam komunitas
politik, kewarganegaraan demokratis, dan kemandirian dari suatu ranah publik yang
bertindak sebagai sistem perantara antara negara dan masyarakat. Habermas
menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan dialog di media dalam mewujudkan
demokrasi yang deliberatif. Dialog di media ini idealnya dapat digunakan sebagai bahan
pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, dalam pandangan
ini, legitimasi dari demokrasi tidak hanya bergantung dari proses perumusan kebijakan,
tetapi juga pada “kualitas diskursif dari proses pertimbangan yang mendalam yang
membawa pada hasil tersebut.”
UniversityDiscourse
Master Discourse Hysteric Discourse Analyst Discourse
308
267
402
23
Sebaran Struktur Wacana
22
Poin penting yang perlu digarisbawahi dari teori ini adalah bahwa dengan
berkurangnya hambatan‐hambatan bagi partisipasi dalam bahasan publik dan
meningkatnya demokratisasi dapat memberikan peluang bagi munculnya aksi‐aksi sosial
yang lebih terbuka. Oleh karena itu, dengan meningkatnya partisipasi dalam
pembahasan demokrasi di media, diyakini pula bahwa aksi‐aksi sosial yang merupakan
penunjang demokrasi akan dapat meningkat.
Pendekatan ini menekankan bahwa terwudunya demokrasi partisipatoris penting
untuk dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Dengan
diwujudkannya demokrasi partisipatoris, yakni demokrasi dimana rakyat juga dapat
berpartisipasi dengan lebih luas (termasuk dalam media), maka peningkatan demokrasi
akan semakin tinggi, karena rakyat dapat mengawasi sekaligus memberikan tinjauan /
masukan terhadap kinerja para elit politik. Hal ini juga diharapnya akan membentuk
masyarakat yang lebih kritis dan peduli terhadap wacana‐wacana demokrasi, sehingga
mereka akan lebih aktif dalam diskusi seputar demokrasi di media.
Sayangnya, pendekatan ini terlalu mengasumsikan banyak hal. Misalnya tentang
primasi kualitas diskursif, yang oleh Habermas dimaknai sebagai rasionalitas. Adalah
corak dari rasionalitas itu yang tidak dipertanyakan oleh Habermas. Bahkan,
sebagaimana ditunjukkan studi ini, rasionalitas dalam diskursus adalah selalu ditentukan
oleh aspek irasional, yaitu hasrat, yang dalam studi ini dijabarkan ke dalam 12 tipe. Dalam
rupa‐rupa rasionalisasi artikulasi di “ruang publik”—untuk menggunakan term
Habermas dan para teoritisi media baru yang Habermasian—subyek telah selalu
memproyeksikan hasrat mereka.
Habermas dan para pendukung demokrasi partisipatoris delibaratif ini telah
mencampuradukkan antara partisipasi kongkrit dalam artian formal dan dalam artian
yang sensasi. Seseorang, untuk menggunakan seluruh kemampuan rasionalnya dalam
berpartisipasi pada proses‐proses demokrasi di ruang publik, tidak selamanya dituntun
oleh kepentingan yang rasional. Malahan, rasionalitas itu sendiri merupakan bentuk
penampakan dari hasrat‐hasrat yang sifatnya irasional. Mencampur‐adukkan keduanya
akan membuat kita terjebak pada penjunjung‐tinggian naif akan proses‐proses
demokrasi. Tanpa pernah mempertanyakan apakah proses‐proses tersebut benar‐benar
dihasrati atau hanya sekedar alat pemuas hasrat lainnya yang notabene eksternal dari
demokrasi itu sendiri. Hal ini akan ditunjukkan melalui diskusi berikut.
Sensasi Partisipasi Demokrasi
Secara umum, dengan melihat obyek hasrat yang dominan muncul, yaitu pemilu
itu sendiri (521, 52%) dan para kandidatnya (195, 20%) maka hal ini menunjukkan betapa
masyarakat kebanyakan menghasrati akan suatu pemilu berikut kandidat yang ideal.
Kedua obyek ini, apabila dilihat dari temuannya, diartikulasikan melalui struktur hasrat
histeris (Pilkada 57% dan pasangan 21%).
23
Kenyataan dominannya struktur histeris ini menunjukkan bahwa terdapat ketidak‐
puasan terhadap dua obyek hasrat ini—pilkada dan pasangan. Tingginya struktur
histeris, dengan demikian dapat diartikan bahwa orang menyalurkan hasratnya dengan
cara mengkritisi, memaki, mencaci, mengolok, mencemooh, menyumpahi bahkan
mengutuk kedua obyek ini. Sekali lagi, hal ini harus diartikan bahwa hasrat masyarakat
dominan terpoyeksikan dalam bentuk negatif ke arah pilkada dan pasangan itu sendiri.
Dengan melampiaskan kekesalan mereka terhadap keduanya melalui hasrat histerik,
maka mereka mendapat kepuasan, via negativa.
Kepuasan apakah yang dikejar? Hal ini penting untuk melihat identitas hasrat
macam apa saja yang dominan memotivasi struktur histerik.
29%
30%
38%
3%
Sebaran Struktur Wacana pada Tweets Berobjek Pilkada/Pilgub
University
Master
Hysteric
Analyst
Pilkada57%
Pasangan21%
Jkt / Ind7%
Demokrasi6%
Other9%
Obyek Hasrat per Struktur Histerik
24
Sebagaimana disajikan di atas maka tampak dengan jelas dua bentuk yang amat
dominan, yaitu hasrat anaklitik‐aktif‐simbolik (218, 54%) dan hasrat anaklitik‐aktif
imajiner (147, 37%). Hal ini menunjukkan dua hal. Pertama, tingginya identitas hasrat aktif
dan anaklitik ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia telah merasa kehilangan
sesuatu yang mereka miliki. Kehilangan ini bisa diartikan sebagai kedua obyek hasrat
yang dibahas sebelumnya. Melalui wacana ini, mereka kemudian berusaha
memproyeksikan hasratnya pada rupa‐rupa wacana histerik mereka. Mereka meminta.
Meminta, dalam struktur histeris, juga berarti memperdengarkan permintaan. Artinya, yang
mereka tuju adalah didengarnya jeritan mereka.
Kedua, tingginya bentuk simbolik dan imajiner dari kedua macam identitas hasrat
tesebut, berarti pada dua hal: krisis sistesmik dan krisis idealisme. Krisis sistemik
ditunjukkan dengan jelas akan histeria akan hasrat anaklitik‐aktif‐simbolik.
Mengartikulasikan hasrat ini secara histeris, dengan jelas menunjukkan tentang krisis,
kegagalan, kebobrokan, dan kemerosotan sistem ini. Sistem simbolik, yang didamba‐
dambakan sang subyek untuk mengatur dan menjaga keamanan eksistensial mereka,
trebukti gagal. Krisis idealisme, berikutnya, juga bisa dilihat sebagai krisis sosok ideal,
sosok kuat, tegas dan pengayom yang mampu mengurusi para subyek. Permintaan
terhadap sosok inilah yang menjelaskan tingginya proyeksi hasrat ke arah pasangan
kandidat. Kandidat‐kandidat inilah yang nantinya, jika terpilih, dibebankan tugas untuk
mengurusi dan mengayomi mereka (baca: mengurai kemacetan dan mengurusi banjir).
Di sini perlu diperjelas. Bukan para kandidat itu yang dituju para subyek hasrat,
melainkan adalah kemampuan mereka untuk mengakomodir gagasan ideal yang
dihasrati para subyek tersebut. Inilah, pada gilirannya, pentingnya kampanye politik,
yaitu untuk meyakinkan calon pemilih bahwa mereka, dalam bahasa psikoanalisis,
mampu memuaskan hasrat pemilihnya.
Untuk mengkontraskan ini, maka perlu juga untuk melihat kecenderungan minor
lainnya. Yaitu, kenyataan bahwa artikulasi hasrat histeris tersebut amat sedikit yang
dinyatakan ke demokrasi (6%) itu sendiri, dan kota/negara (7%). Hal ini menunjukkan
dengan jelas bahwa bagi masyarakat, yang bermasalah adalah orang dan
aparatur/birokratik sistemiknya! Mereka tidak melihat kesalahan pada sistem demokrasi
1% 1% 0%
37%
54%
0%
1%
0%0%
4%2%
0%
Motivasi Hasrat melalui Sruktur Histerik
Aktif‐Narsistik‐Imaginer
Aktif‐Narsistik‐Simbol
Aktif‐Narsistik‐riil
Aktif‐anaklitik‐Imaginer
Aktif‐anaklitik‐Simbol
Aktif‐Analcitic‐riil
Pasif‐Narsistik‐Imaginer
Pasif‐Narsistik‐Simbol
25
dan atau negara itu sendiri. Ini menunjukkan betapa parokhial dan reaksionernya
masyarakat dalam memahami permasalahan. Yang mereka cela adalah hal‐hal yang
menjadi immediate concern mereka. Padahal, bisa saja ada yang salah dengan sistem
demokrasi itu sendiri, dan / atau penyelenggaraan negara, yang menjadi ujung pangkal
segala permasalahan yang mereka keluhkan melalui histeria.
Menyusul skor histeris adalah struktur universitas. Struktur universitas ini juga
didominasi oleh hasrat aktif‐anaklitik‐simbolik (124) dan aktif‐anaklitik‐imajiner (120),
dengan perolehan berimbang di antara keduanya, yaitu 40%‐30%. Pola kecenderungan
seperti ini bisa dimaklumi semenjak ia didahului oleh tingginya histeria. Berseiringan
dengan munculnya keluhan‐keluhan dalam histeria, selalu dibarengi dengan munculnya
wacanan‐wacana yang mencoba menjadi penawar dan pelipur‐lara, jika bukan pelarian,
dari keluhan tersebut. Persis di sinilah wacana universitas muncul.
Struktur naratif wacana universitas selalu mencoba menambal lack yang ada pada subyek
dengan sutau janji‐janji yang kekal, universal, absolut, dst. Ide‐ide ideal seperti bijak, baik,
adil, sentosa, pengayom, dst., akan selalu coba ditawarkan bagi subyek‐subyek histerik
ini.
Hal ini berbahaya, karena akan membawa artikulasi politik dalam demokrasi ke
hal‐hal yang sifatnya moralistik dan etis. Akhirnya, perjuangan politik tidak ubahnya
menjadi medan kontestasi khotbah‐khotbah moral dan nasihat‐nasihat etis. Semua orang
berlomba‐lomba untuk menasihati satu sama lain. Tidak sedikit, sebagaimana data
temuan kami, yang menggunakan agama untuk menjustifikasinya. Bagi yang “sekuler”
pun juga memobilisasi filsafat‐filsafat, penyair‐penyair, dan para teoritikus mereka untuk
mengutarakan nasihat‐nasihat mereka. Yang lainnya, akan terjebak dengan menyuarakan
puisi‐puisi merdu, lantunan doa, dan kutipan‐kutipan inspirasional. Alhasil, problem‐
problem kongkrit di lapangan tidak akan pernah tersentuh, apalagi terpecahkan. Politik
demokrasi pun akhirnya menjadi “seminar Mario Teguh.”
3% 1% 0%
40%
39%
0%
1%
0%0%
10%
6% 0%
Motivasi Hasrat melalui Struktur Universitas
Aktif‐Narsistik‐Imaginer
Aktif‐Narsistik‐Simbol
Aktif‐Narsistik‐riil
Aktif‐anaklitik‐Imaginer
Aktif‐anaklitik‐Simbol
Aktif‐Analcitic‐riil
Pasif‐Narsistik‐Imaginer
Pasif‐Narsistik‐Simbol
26
Menjadi parah lagi saat ini diproyeksikan ke sosok pemimpin. Pemimpin yang
memproyeksikan hasrat berstruktur universitas ini, dan yang kepadanya diproyeksikan
hasrat anaklitik‐simbolik maupun anakltik‐imajiner ini berpotensi untuk menjadi otoriter
dan totaliter. Hal ini demikian, dengan mengokupasi posisi absolut, ia menjadi tidak
dipertanyakan lagi. Kualitas‐kualitas yang perlu ia tonjolkan adalah karisma belaka.
Persis seperti ratu‐adil/mesias yang menyelamatkan umat manusia. Akhirnya, politik
demokrasi tidak lebih dari ritual relijius untuk menyembah masing‐masing jago
kandidatnya.
Di sini pentingnya untuk sekali lagi untuk mendedah identitas hasrat dari bentuk
kongkrit obyek hasrat, maka dapat diketahui bahwa yang sebenarnya dikejar oleh
seseorang saat ia melakukan prilaku partisipasi demokrasi, sebenarnya bukan partisipasi
itu sendiri, melainkan apa yang akan disebut ‘sensasi partisipasi demokrasi’ itu sendiri.
Sensasi partisipasi demokrasi merupakan motivasi libidinal subyek untuk melakukan
partipasi demokrasi. Sekali lagi, bukan partisipasi demokrasi yang dipentingkan,
melainkan sensasi memperoleh identitas hasrat apa yang mampu ia ekstrak saat ia
menjalankan simtom partisipasi demokrasi tersebut.
SIMPULAN
Penelitian ini berangkat dari sebuah paradoks dalam kehidupan berdemokrasi di
Indonesia hari‐hari ini: maraknya kehadiran media massa, terutama media baru, berikut
intensitas penggunaan yang super tinggi di satu sisi, sementara maraknya opini publik
tentang demokrasi yang belum benar‐benar diimplementasikan, bahkan tidak sedikit
yang secara pesimis menilainya sebagai kegagalan. Jadi, di satu sisi terdapat surplus
media, dan di sisi lain terdapat defisit demokrasi. Kenyatan inilah yang disebut sebagai
‘paradoks demokratisasi di era media baru’. Paradoks ini akan berubah menjadi suatu
anomali saat ia dibenturkan dengan teori klasik yang menekankan peran media sebagai
pilar keempat demokrasi (setelah eksekutif, legistlatif dan yudikatif). Media, diyakini
menjadi prasyarat mutlak sekaligus indikator penting bagi terselenggaranya demokrasi.
Dengan latar belakang teoritik seperti ini, dengan demikian penelitian ini mengajukan
pertanyaan, “Mengapa di era keterbukaan informasi dimana hampir seluruh orang dapat
mengartikulasikan pendapatnya secara bebas melalui media, malah muncul wacana
defisit demokrasi?”
Argumentasi yang diuji oleh penelitian ini adalah bahwa media tidak serta merta
menjadi faktor penentu sukses tidaknya demokrasi, telah terbukti. Yaitu bahwa ada
faktor‐faktor lainnya yang menjadi ‘variabel antara’ di antara partisipasi media dan
demokrasi, yang juga dapat mempengaruhi mengapa demokrasi media masih sangat
kurang. Faktor lain tersebut hanya bisa dipahami apabila meletakkan prilaku partisipasi
masyarakat dalam proses demokrasi sebagai modus artikulasi pemuasan hasrat, atau
yang disebut simtom. Melalui identifikasi simtom dominan, studi ini mencoba mampu
menunjukkan identitas hasrat apa yang sebenarnya dikejar saat seseorang berpartisipasi
dalam proses demokrasi.
27
Dengan meletakkan seperti ini, maka menjadi terbuka peluang untuk
mengidentifikasikan faktor lain tadi. Dengan mendedah identitas hasrat dari bentuk
kongkrit obyek hasrat, maka dapat diketahui bahwa yang sebenarnya dikejar oleh
seseorang saat ia melakukan prilaku partisipasi demokrasi, sebenarnya bukan partisipasi
itu sendiri, melainkan apa yang akan disebut ‘sensasi partisipasi demokrasi’ itu sendiri.
Sensasi partisipasi demokrasi merupakan motivasi libidinal subyek untuk melakukan
partipasi demokrasi. Sekali lagi, bukan partisipasi demokrasi yang dipentingkan,
melainkan identitas hasrat apa yang mampu ia ekstrak saat ia menjalankan simtom
partisipasi demokrasi tersebut.
Keslaah‐mengiraan antara sensasi dengan realitas inilah yang memungkinkan
terjadinya pengalihan (diversionary) partisipasi demokrasi. Adalah media baru, klaim
kami, yang mampu melakukan kerja pengalihan ini. Melalui media baru, energi‐energi
subyek hasrat yang melakukan partisipasi demokrasi tadi dialihkan untuk terus menerus
merepetisi proses kongkrit partisipasi tadi melalui media baru. Partisipasi, akhirnya
menjadi sebentuk ritual fetis. Subyek hasrat terjebak dalam sirkuit partisipasi demokrasi
yang terus menerus berepetisi. Akhirnya, energi yang seharusnya disalurkan ke
permasalahan‐permasalahan kongkrit di lapangan menjadi terbendung dan terjebak di
sirkuit media baru. Dengan beghini, menjadi masuk akal paradoks demokrasi di era
media baru yang kami sampaikan di atas. Ketiadaan perubahan signifikan di lapangan,
bukan karena absennya partisipasi. Ia terjadi karena telah terjadi pengalihan dan
penjebakan energi partisipasi secara besar‐besaran ke dalam sirkuit‐sirkuit media baru.
Dan semenjak yang sebenarnya dibutuhkan subyek dalam berpartisipasi adalah hanya
sensasinya saja (sensasi memperoleh identitas hasrat yang ditujunya), maka ia akan terus
terjebak tunggang‐langgang dalam sikuit media baru, sementara demokrasi riil akan
semakin defisit dan defisit, ... menyisakan pemimpin‐pemimpin otoriter.
Penelitian ini memiliki implikasi teoritis, terutama pada pergeseran (jika memang
terjadi) konsep tentang partisipasi pada demokrasi. Lebih jauh lagi, konsep demokrasi
partisipatoris menuntut banyak modifikasi (jika bukan harus ditinggalkan) untuk bisa
tetap relevan di era kontemporer di mana terjadi ledakan media baru. Pada akhirnya, ia
juga akan berimplikasi pada gagasan demokrasi itu sendiri, yaitu tentang apa artinya
berdemokrasi di era dimana media justru menjadi penghalang demokrasi. Lebih lanjut,
argumen tim peneliti dalam proposal ini adalah bahwa teori fourth estate democracy yang
diajukan oleh Burke salah mengartikan karakteristik dari komunikasi di era kontemporer.
Oleh karena itu, kami melihat bahwa teori fourth estate democracy tersebut menjadi tidak
relevan dengan kondisi saat ini dan perlu untuk dipertimbangkan kembali dimensi
partisipatoris dari media dalam teori tersebut.