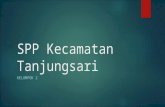RANCANGAN MODEL SISTEM PERTANIAN BERKELANJUTAN (SPT) PADA AGROEKOSISTEM LAHAN KERING DI DESA...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of RANCANGAN MODEL SISTEM PERTANIAN BERKELANJUTAN (SPT) PADA AGROEKOSISTEM LAHAN KERING DI DESA...
RANCANGAN MODEL SISTEM PERTANIAN BERKELANJUTAN (SPT) PADA
AGROEKOSISTEM LAHAN KERING DI DESA MARGAJAYA, KECAMATAN
TANJUNGSARI, KABUPATEN SUMEDANG, JAWA BARAT
DISUSUN OLEH:
Shania Al Syamsi 1505100110099
Puspita Argha 1505100110111
Daniel H. Pasaribu 1505100110121
Fatahany Fadhila 1505100110126
Netta Eka Safitri 1505100110130
AGROTEKNOLOGI I
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN
2014
Abstrak
Desa Margajaya terletak di Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang,
Jawa Barat berada di dataran rendah dan didominasi oleh pertanian lahan kering.
Pertanian lahan kering merupakan sumber mata pencaharian mayoritas penduduk
Desa Margajaya. Pengolahan lahan yang kurang mempertimbangkan kaidah
pertanian berkelanjutan, olah tanah intensif pada lahan kering, penggunaan pupuk
dan pestisida kimia merupakan praktek budidaya pertanian yang masih ditemui.
Penerapan prinsip – prinsip pertanian berkelanjutan perlu ditingkatkan mengingat
pentingnya untuk menjaga lingkungan. Bagaimanakah upaya yang dapat
direncanakan untuk meningkatkan pertanian berkelanjutan di Desa Margajaya?
Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan perencanaan peningkatan penerapan
prinsip – prinsip pertanian berkelanjutan di Desa Margajaya dan menggunakan
prinsip LEISA (Low External Input Suistanable Agriculture).
Dengan masukan sarana produksi rendah atau LEISA ini, tidak menggunakan
bahan kimia tetapi memakai bahan-bahan organik berdasarkan prinsip daur ulang
yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi setempat. Usaha tani ini ditujukan untuk
mewujudkan banyak aspek yaitu pertanian yang ekonomis, ekologis, dan
berbudaya adalah semua faktor penting dapat dimasukkan dalam struktur hierarki,
kemudian diatur berdasarkan urutan prioritas yang terpenting dan terbaik. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa masih banyaknya lahan di Desa Margajaya yang
belum menerapkan sistem LEISA, namun sudah terdapat beberapa sistem
agroindustri.
Kata Kunci : Sistem Pertanian Berkelanjutan, LEISA, Desa Margajaya.
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha
Esa. Karena, berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis mampu
menyelesaikan laporan akhir yang berjudul “Rancangan Model
Sistem Pertanian Berkelanjutan (SPT) pada Agroekosistem
Lahan Kering di Desa Margajaya, Kecamatan Tanjungsari,
Kabupaten Sumedang, Jawa Barat”. Laporan ini disusun untuk
memenuhi salah satu tugas akhir mata kuliah Sistem Pertanian
Berkelanjutan.
Tim penulis menyadari, bahwa selama penulisan makalah ini
tim penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab
itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :
1. Dosen mata kuliah yang telah membimbing dalam menyusun
makalah ini;
2. anggota kelompok yang telah membantu dalam menyusun
makalah ini; dan
3. semua pihak yang tidak bisa tim penulis sebut satu
persatu.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan berlipat
ganda.
Makalah ini bukan karya yang sempurna, karena masih
memiliki banyak kekurangan, baik dalam hal isi maupun
sistematika dan tekhnik penulisannya. Oleh sebab itu,
penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun
demi kesempurnaan makalah ini. Akhirnya, semoga makalah ini
bisa memberikan manfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Amin.
Jatinangor, Desember 2014
DAFTAR ISI
Abstrak
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
1.2. Identifikasi Masalah
1.3. Tujuan Penelitian (Survei)
1.4. Kegunaan Penelitian (Survei)
BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1. Konsep Pertanian Berkelanjutan (SPT)
2.2. Konsep Agroekosistem
2.3. Konsep LEISA dan Pemanfaatan Sumber Daya Lokal
2.4. Pola Tanam dalam Pertanian Berkelanjutan
BAB III METODOLOGI
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian (Survei)
3.2. Diagram Alur Proses Penilaian Kondisi-Eksis
3.3. Proses Pengumpulan Data
3.4. Metode Analisis Data (Deskriptif)
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian (Survei)
4.2. Potensi Sumber Daya Alam Lokasi Survei (Kekayaan dan
Sifat Agoekosistem)
4.3. Pelaksanaan Sistem Pertanian/Sistem Usahatani di Lokasi
Survei
BAB V RANCANGAN MODEL SISTEM PERTANIAN BERKELANJUTAN (SPT) DI
LOKASI SURVEI
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
1.2 Identifikasi Masalah
1. Bagaimana keadaan agroekosistem di Desa Margajaya?
2. Apa saja potensi serta kearifan lokal yang ada di Desa
Margajaya?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam sistem pertanian
di Desa Margajaya?
4. Bagaimana rekomendasinya terhadap permasalahn yang ada
di Desa Margajaya?
1.3 Tujuan Penelitian
1. Mengetahui keadaan agroekosistem di Desa Margajaya
2. Mengetahui potensi serta kearifan lokal yang ada di
Desa Margajaya
3. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam sistem pertanian
di Desa Margajaya
4. Menyusun rekomendasi untuk pemecahan masalah.
1.4 Kegunaan Penelitian
Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan
memperoleh informasi atau data mengenai Desa Margajaya serta
potensi yang terdapat disana dan memberikan saran
rekomendasi pada permasalahan yang terdapat di sana.
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1. Konsep Pertanian Berkelanjutan (SPT)
Paradigma pembangunan berkelanjutan menurut Bank Dunia
diterjemahkan dalam bentuk kerangka segitiga pembangunan
berkelanjutan (Environmentally Sustainable Development Triangle) yang
bertumpu pada keberlanjutan ekonomi, ekologi, dan sosial.
Berkelanjutan secara ekonomis mengandung pengertian bahwa
suatu kegiatan pembangunan harus mampu menghasilkan
pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan kapital, penggunaan
sumberdaya, serta investasi secara efisien. Berkelanjutan
secara ekologis berarti bahwa kegiatan tersebut mampu
mempertahankan integritas ekosistem, memelihara daya dukung
lingkungan, dan konservasi sumberdaya alam termasuk
keanekaragaman hayati (biodiversity). Keberlanjutan secara
sosial diartikan bahwa pembangunan tersebut dapat menciptakan
pemerataan hasil – hasil pembangunan, mobilitas sosial,
kohesi sosial, partisipasi masyarakat, pemberdayaan
masyarakat, identitas sosial, dan pengembangan kelembagaan
(Serageldin, 1996 dalam Dahuri 1998).
Pertanian berkelanjutan mempunyai beberapa prinsip yaitu :
(a) menggunakan sistem input luar yang efektif, produktif,
murah, dan membuang metode produksi yang menggunakan sistem
input dari industri, (b) memahami dan menghargai kearifan
lokal serta lebih banyak melibatkan peran petani dalam
pengelolaan sumberdaya alam dan pertanian, (c) melaksanakan
konservasi sumberdaya alam yang digunakan dalam sistem
produksi (Shepherd, 1998 dalam Budiasa, 2011). Persoalan yang
sering dihadapi dalam mewujudkan pertanian berkelanjutan
adalah adanya tarik - menarik antara berbagai kepentingan
pembangunan. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan
pertanian berkelanjutan antara lain faktor sosial, ekonomi,
dan kelembagaan (Purwanto dan Cahyono, 2012); faktor pilihan
teknis konservasi yang tepat, sesuai dengan latar belakang
sosial, ekonomi, budaya masyarakat (Sabiham dalam Arsyad, S.
dan E. Rustiadi, 2008); faktor individu, ekonomi, dan
kelembagaan (Illkpitiya dan Gopalakrishnan, 2003); faktor
kelembagaan, kebijakan pemerintah, dan perubahan teknologi
(Ananda dan Herath, 2003). Bagaimanakah upaya untuk
menselaraskan berbagai aspek kepentingan dengan tetap menjaga
kelestarian lingkungan merupakan tantangan dalam mewujudkan
pembangunan pertanian berkelanjutan.
Desa Margajaya terletak di Kecamatan tanjung sari dan
berada di dataran rendah dengan ketinggian 890 dpl yang
terdiri atas 106 Ha sawah, 86,6 Ha lahan bukan sawah dan 3,7
lahan bukan pertanian. Daerah ini didominasi oleh pertanian
lahan kering yang merupakan sumber mata pencaharian mayoritas
penduduk Desa Margajaya. Komoditas utama yang dikembangkan
oleh petani Desa Margajaya adalah berbagai jagung, ubi kayu,
dan singkong. Pola budidaya tanaman semusim pada beberapa
tanaman pangan tersebut ternyata masih ditemukan penggunaan
pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan. Prinsip penggunaan
pestisida kimia yang dilakukan adalah preventif untuk mencegah
berkembangnya hama penyakit agar tidak rugi karena kehilangan
hasil panen. Pengolahan limbah pertanian atau peternakan masih
kurang maksimal dilakukan meskipun pemanfaatan pupuk kandang
sudah umum dilakukan. Berdasarkan kenyataan yang demikian maka
peningkatan penerapan prinsip - prinsip pertanian
berkelanjutan perlu dilakukan.
Menurut Salikin (2003), bahwa sistem pertanian
berkelanjutan dapat dilaksanakan menggunakan berbagai model
antara lain sistem pertanian organik, integrated farming,
pengendalian hama terpadu, dan LEISA (Low External Input Sustainable
Agriculture). Sistem pertanian organik merupakan sistem produksi
pertanian yang menjadikan bahan organik sebagai faktor utama
dalam proses produksi usahatani. LEISA adalah pertanian yang
mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dan manusia
setempat/lokal, layak secara ekonomis, mantap secara ekologis,
sesuai dengan budaya, adil secara sosial, dan input luar hanya
sebagai pelengkap (Reijntjes et al. 1999). Integrated pest
management atau pengelolaan hama terpadu merupakan suatu
teknologi pengendalian hama yang bertujuan untuk memaksimalkan
efektivitas pengendalian secara biologi dan budaya.
Pengendalian secara kimia dilakukan dengan meminimalkan
gangguan terhadap lingkungan (Luna dan House, 1990 dalam
Budiasa, 2011).
Mengingat Desa Margajaya memiliki potensi lahan kering dan
hanya ditanami pada musim penghujan saja, maka diperlukannya
suatu sistem yang cocok dengan kondisi lahan di Desa
Margajaya. Sistem pertanian LEISA cocok dikembangkan di desa
ini karena input yang diberikan pada pola tanam beberapa
komoditas pangan ini harus diperhatikan dengan pemanfaatan
bahan organik yang potensinya sudah tersedia seperti limbah
pertanian dan peternakan.
2.2. Konsep Agroekosistem
Dari tinjauan historis menurut sudut pandang
pendayagunaan sumberdaya lahan, pola penggunaan tanah di
Indonesia telah berubah dari pola ekstensif alamiah (hutan,
semak, dan padang penggembalaan) ke pola yang relatif
intensif. Pola penggunaan tanah untuk usaha pertanian
dapat dipilah menjadi dua: (a) usaha pertanian skala besar
yang umumnya berupa perkebunan yang dikelola oleh badan usaha
milik negara maupun perusahaan swasta, (b) usaha pertanian
rakyat. Meskipun usaha pertanian rakyat umumnya menerapkan
pola campuran, tetapi menurut komoditas dominan yang
diusahakannya secara garis besar dapat dipilah lebih lanjut
menjadi dua kategori: (i) usaha pertanian tanaman
pangan/hortikultura dan (ii) perkebunan rakyat.
Terkait dengan orientasi kebijakan pengembangan pertanian
rakyat yang selama ini ditempuh, perkembangan pertanian paling
maju adalah pada agroekosistem pesawahan yakni dalam usahatani
padi. Pada usahatani berbasis lahan kering usahatani yang
paling berkembang adalah pada usahatani tanaman perkebunan,
usahatani komoditas sayuran bernilai ekonomi tinggi dan
peternakan khususnya unggas. Khususnya untuk usahatani sayuran
dan peternakan, kemajuannya cenderung spesifik lokal dalam
arti perkembangan yang cukup nyata adalah di sentra-sentra
produksi sedangkan di wilayah non sentra produksi kurang
berkembang.
Penciri agroekosistem tidak hanya mencakup unsur-unsur
alami (iklim, topografi, altitude, fauna, flora, jenis tanah,
dan sebagainya) tetapi juga unsur-unsur buatan. Bahkan dalam
pendekatan pragmatis yang lazim digunakan mengarah pada unsur-
unsur buatan. Sumaryanto dkk (2008) membedakan agroekosistem
menjadi 3: (1) pesawahan, (2) lahan kering (terdiri dari:
lahan kering berbasis tanaman pangan/hortikultura, dan lahan
kering berbasis tanaman perkebunan), dan (3) agroekosistem
pesisir.
Penggunaan istilah ”lahan kering” di Indonesia belum
tersepakati secara aklamasi. Beberapa pihak menggunakan untuk
padanan istilah Inggris: upland, dryland, atau non irrigated land
(Notohadiprawiro, 1989). Kadekoh (2010) mendefinisikan lahan
kering sebagai lahan dimana pemenuhan kebutuhan air tanaman
tergantung sepenuhnya pada air hujan dan tidak pernah
tergenang sepanjang tahun. Istilah yang biasa dipergunakan
untuk pertanian lahan kering adalah pertanian tanah darat,
tegalan, ladang, tadah hujan dan huma.
Sementara menurut Minardi (2009), lahan kering umumnya
selalu dikaitkan dengan pengertian bentuk-bentuk usahatani
bukan sawah yang dilakukan oleh masyarakat di bagian hulu
suatu Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai lahan atas (upland)
atau lahan yang terdapat di wilayah kering (kekurangan air)
yang tergantung pada air hujan sebagai sumber air. Definisi
lahan kering menurut Direktorat Perluasan areal (2009) adalah
“hamparan lahan yang tidak pernah tergenang atau digenangi air
pada sebagian kecil waktu dalam setahun, yang terdiri dari
lahan kering datarang rendah dan lahan kering dataran tinggi”.
Prospek agroekosistem lahan kering untuk pengembangan
peternakan cukup baik (Bamualim, 2004). Peluang pasarnya masih
sangat terbuka. Kemampuan pasar domestik untuk menyerap
produksi yang dihasilkan dari usaha peternakan sapi pedaging,
sapi perah, kambing. domba, babi, unggas (ayam, burung puyuh)
masih akan terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah
penduduk dan pendapatan per kapita. Bahkan dalam rangka
mengurangi ketergantungan impor, perlu ada program dan aksi
nyata yang revolusioner.
Berkembangnya kebutuhan pangan utama membutuhkan
perluasan areal untuk pengembangan tanaman pangan dan
perkebunan. Salah satu akibatnya terjadi kompetisi penggunaan
lahan diantaranya antar subsektor dalam sektor petanian.
Beberapa pihak beranggapan lahan penggembalaan merupakan lahan
tidur sehingga perlu diefektifkan pemanfaatannya. Pola pikir
yang demikian memperkecil sumberdaya alam yang sebenarnya
merupakan basis pengembangan usaha peternakan .
Lahan kering mempunyai potensi besar untuk pengembangan
pertanian, baik tanaman pangan, hortikultura, maupun tanaman
tahunan/perkebunan. Pengembangan berbagai komoditas pertanian
di lahan kering merupakan salah satu pilihan strategis untuk
meningkatkan produksi dan mendukung ketahanan pangan nasional
(Mulyani dkk, 2006). Namun demikian, tipe lahan ini umumnya
produktivitasnya rendah, kecuali pada lahan yang dimanfaatkan
untuk tanaman tahunan/perkebunan. Pada usahatani lahan kering
dengan tanaman semusim, produktivitas relatif rendah serta
menghadapi masalah sosial ekonomi seperti tekanan penduduk
yang terus meningkat dan masalah biofisik (Sukmana, dalam
Syam, 2003).
Pada umumnya sistem pertanian lahan kering belum dipahami
secara mendalam, sementara keragaman ekosistemnya cukup
kompleks. Kendala lingkungan, kondisi sosial ekonomi
masyarakat, serta keterbatasan sentuhan teknologi yang adaptif
mengakibatkan kualitas, produktivitas dan stabilitas sistem
usahatani yang ada masih terbatas (Guritno, et al, 1997).
Kerusakan fungsi lahan sebagai media tumbuh, seperti pekanya
tanah terhadap erosi, unsur hara yang minim, terbatasnya
kandungan bahan organik merupakan permasalahan biofisik. Di
lain pihak petani lahan kering merupakan petani yang tergolong
marginal yang ditandai dengan pendapatan dan pendidikan
rendah, ketrampilan terbatas, dan terbatasnya pelaksanaan
kondervasi pada lahan usahataninya (Sholahuddin dan Ladamay,
dalam Kadekoh 2010). Hal ini merupakan masalah-masalah klasik
di kalangan petani lahan kering yang memerlukan penanganan
yang optimal, terencana dan berkelanjutan.
Untuk menciptakan prospek cerah, khususnya bagi lahan kering,
menurut Notohadiprawiro (1989), diperlukan teknologi sepadan
(apprioritas), baik bagi lingkungan biofisik maupun bagi
lingkungan sosial ekonomi. Teknologi yang dipandang tepat
adalah berasaskan LEISA (Low External Input Sustainable Agriculture).
2.3. Konsep LEISA dan Pemanfaatan Sumber Daya Lokal
Pertanian organik merupakan suatu sistem pertanian yang
berazaskan daur ulang hara secara hayati. Pertanian organik
juga sering dikatakan sebagai pertanian yang menerapkan
masukan teknologi berenergi rendah LEISA (Low External Input
Sustainable Agriculture). Di kalangan petani relatif masih sedikit
yang bersedia menerapkan pertanian organik karena dari segi
produksi memang lebih rendah tetapi dari segi harga jual jauh
lebih mahal. Prospek pengelolaan lingkungan dalam pertanian
ramah lingkungan seharusnya mengacu pada konsep LEISA. LEISA
mengacu pada bentuk-bentuk pertanian sebagai berikut
(Reijntjes, 1999):
a) Berusaha mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal yang
ada dengan mengkombinasikan berbagai macam komponen sistem
usaha tani, yaitu tanaman, hewan, tanah, air, iklim, dan
manusia sehingga saling melengkapi dan memberikan efek
sinergi yang paling besar.
b) Berusaha mencari cara pemanfaatan input luar hanya bila
diperlukan untuk melengkapi unsur-unsur yang kurang dalam
ekosistem dan meningkatkan sumberdaya biologi, fisik, dan
manusia. Dalam memanfaatkan input luar, perhatian utama
diberikan pada maksimalisasi daur ulang dan minimalisasi
kerusakan lingkungan.
LEISA tidak bertujuan untuk memaksimalkan produksi dalam
jangka pendek, namun untuk mencapai tingkat produksi yang
stabil dan memadai dalam jangka panjang. LEISA berupaya untuk
mempertahankan dan dimana mungkin, meningkatkan sumberdaya
alam serta memanfaatkan secara maksimal proses-proses alami.
Di mana bagian dari produksi itu dipasarkan, maka dicari
peluang untuk memperoleh kembali unsur hara yang dihilangkan
dari sistem usaha tani ke pasar. Dengan kata lain LEISA dapat
dikatakan sebagai suatu konsep yang terpadu dan lintas
sektoral, menekan penggunaan input dari luar sehingga
mengoptimalkan penggunaan input internal dan akan diperoleh
suatu sistem usaha pertanian yang efisien dan berdaya saing
global.
Keuntungan yang akan diperoleh dari konsep LEISA adalah:
a) Usaha pertanian yang terpadu
b) Usaha pertanian yang berbasis lokal sehingga tahan
terhadap krisis 5
c) Usaha pertanian yang dapat menghasilkan produk organik
yang mempunyai harga lebih baik
d) Usaha pertanian yang mempunyai diversivikasi berbagai
produk sehingga dapat mengurangi resiko kegagalan usaha
Sistem LEISA perlu disosialisasikan kepada para petani di
desa. Pada dasarnya, petani telah memiliki pengetahuan lokal
mengenai ekologi, pertanian dan kehutanan yang terbentuk
secara turun temurun dari nenek moyang mereka dan berkembang
seiring dengan berjalannya waktu. Pengetahuan lokal ini berupa
pengalaman bertani dan berkebun serta berinteraksi dengan
lingkungannya. Pengetahuan lokal yang dimiliki petani bersifat
dinamis, karena dapat dipengaruhi oleh teknologi dan informasi
eksternal antara lain kegiatan penelitian para ilmuwan,
penyuluhan dari berbagai instansi, pengalaman petani dari
wilayah lain, dan berbagai informasi melalui media masa.
Meskipun berbagai teknologi dan informasi masuk ke
lingkungannya, tetapi tidak semua diterima, diadopsi dan
dipraktekkan oleh petani lokal. Sebagai aktor yang paling
mengenal kondisi lingkungan dimana ia tinggal dan bercocok
tanam, petani memiliki kearifan (farmer wisdom) tertentu dalam
mengelola sumber daya alam. Kearifan inilah yang kemudian
menjadi dasar dalam mengadopsi informasi dan teknologi
sehingga menghasilkan pengetahuan lokal yang sesuai dengan
kondisi pertanian setempat (Sinclair dan Walker, 1998).
Pengetahuan lokal merupakan hasil dari proses belajar
berdasarkan persepsi petani sebagai pelaku utama pengelola
sumber daya lokal. Dinamisasi pengetahuan sebagai suatu proses
sangat berpengaruh pada corak pengelolaan sumber daya alam
khususnya dalam sistem pertanian lokal. Seringkali praktek
sistem pertanian lokal dapat memberikan ide yang potensial
dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang ada secara
lestari (Sunaryo dan Joshi, 2003). Dengan demikian, upaya
penggalian pengetahuan lokal untuk menambah khasanah dalam
pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam
perlu dilakukan. Penggalian informasi mengenai pengetahuan
lokal masyarakat dan inovasi yang diadopsi oleh petani dapat
menggambarkan pola pengelolaan sumber daya alam di sekitarnya.
Selain itu, dapat juga dijadikan sebagai input dalam
meningkatkan kehidupan petani, baik dari segi ekonomi, ekologi
dan sosialnya. Pengetahuan lokal dan inovasi yang diadopsi
petani tersebut dikumpulkan, kemudian dirangkai dan dianalisa
menjadi model pengetahuan petani yang lebih terstruktur
sehingga mudah diterapkan oleh masyarakat lain. Model
pemahaman yang dibangun dan dikembangkan petani dapat menjadi
masukan untuk melengkapi dan memperkaya model pengetahuan
ilmiah (scientific models). Dengan demikian, pada saat yang
bersamaan petani dapat menerima dan mengambil manfaat dari
model pengetahuan tersebut untuk mengembangkan pengetahuannya
dan dapat pula diterapkan oleh kelompok petani lain yang belum
mencoba menerapkannya (Joshi et al., 2004).
Pengetahuan lokal suatu masyarakat petani yang hidup di
lingkungan wilayah yang spesifik biasanya diperoleh
berdasarkan pengalaman yang diwariskan secara turun-temurun.
Adakalanya suatu teknologi yang dikembangkan di tempat lain
dapat diselaraskan dengan kondisi lingkungannya sehingga
menjadi bagian integral sistem bertani mereka. Karenanya
teknologi eksternal ini akan menjadi bagian dari teknologi
lokal mereka sebagaimana layaknya teknologi yang mereka
kembangkan sendiri. Pengetahuan praktis petani tentang
ekosistem lokal, tentang sumber daya alam dan bagaimana mereka
saling berinteraksi, akan tercermin baik di dalam teknik
bertani maupun keterampilan mereka dalam mengelola sumber daya
alam. Pengetahuan lokal yang sudah demikian menyatu dengan
sistem kepercayaan, norma dan budaya, dan diekspresikan di
dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu cukup
lama ada kemungkinan akan menjadi suatu ‘kearifan lokal’.
2.4. Pola Tanam dalam Pertanian Berkelanjutan
Peningkatan produktivitas lahan diantaranya dapat dilakukan
melalui penerapan teknologi spesifik lokasi berdasarkan
potensi sumberdaya domestik dengan memperhatikan aspek
lingkungan. Peningkatan produktivitas di lahan kering dapat
dilakukan melalui peningkatan produktivitas per satuan luas
dan peningkatan intensitas pertanaman.
Pengelolaan lahan kering sesungguhnya tidaklah mudah,
karena sangat berkaitan
dengan permasalahan lahan kering yang cukup kompleks baik dari
sumber daya lahannya dan atau sumber daya manusianya. Dari
segi lahannya umumnyasebagai lahan kritis, luas kepemilikan
lahan yang sempit, ketersediaan air tahunanmasih menjadi
kendala terhadap pola pertanaman, tingkat kesuburan yang
rendah,lapisan olah yang rendah dan relatif rentan terhadap
erosi di waktu musim hujan dankesuburan lahan yang rendah.
Lahan kering pada umumnya mempunyai produktivitas tanah dan
tanaman rendah akibat rendahnya tingkat kesuburan tanah dan
curah hujan tidak menentu. Perbaikan sifat fisik, kimia, dan
hayati tanah sawah tadah hujan dapat dilakukan dengan
pemberian pembenah oganik. Salah satu contoh tanaman lokalyang
memliki potensi tumbuh dan berkembang pada lahan kering adalah
kacangtanah ( Arachis hypogeae) dan jagung ( Zea mays). Panen
jagung Indonesia tahun2008 mencapai 4 juta ha dengan rata-rata
pro-duktivitas 4,08 t/ha (Syafruddin et al .,2010). Aspek
komponen produksi pada kacang tanah pada penanaman
jagungdipengaruhi oleh jarak tanam dan perompesan daun jagung
(Zuchri, 2007).
Penanaman campuran merupakan sistem pertanaman dua atau
lebih jenistanaman yang di tanam pada sebidang tanah dengan
musim tanam yang sama.Penanaman campuran memungkinkan terjadi
persaingan selama periode pertumbuhanmaupun hasil produksi
tanaman.
Pertumbuhan penduduk yang padat dan lahan pertanian yang
subur semakin berkurang karena banyak dimanfaatkan sebagai
industri dan tempat pemukiman baru bagi penduduk, merupakan
masalah dalam memenuhi kebutuhan pangan. Menghadapi
permasalahan tersebut maka
sistem pertanian untuk masa depan yang berwawasan lingkungan m
enuju perkembangan berkelanjutan dengan pola tumpangsari perlu
dikembangkan. Sistem pertanaman tumpangsari bertujuan
memperoleh kombinasi tanamanyang sesuai, kepadatan populasi
tanaman, dan mengetahui cara pemupukan yangoptimal. Pola tanam
tumpangsari umumnya untuk mengetahui pemanfaatan cahaya,air,
dan hara. Produktivitas lahan pada sistem tumpangsari
dihitungberdasarkan Nisbah Kesetaraan Lahan (NKL).
Keuntungan pola tanam tumpangsari diantaranya populasi tana
man dapat diatur, efisiensi
pemanfaatan lahan, dan dapat menekanserangan hama serta
penyakit. Peluang pengembangan kacang tanah dan jagung masih
terbuka luasdiantaranya masih tersedia lahan yang cukup luas,
meningkatnya kebutuhan danindustri olahan kacang tanah dan
jagung, tersedianya pasar yang cukup besar, sertatersedianya
benih unggul dan penerapan teknologi terkait perkembangan
agribisnisaneka kacang. Budidaya tanaman koro pedang tergolong
mudah karena dapat tumbuh dilingkungan dengan kesuburan kurang
dan lahan kering.
BAB III
METODOLOGI
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian (Survei)
Kegiatan survei lapangan dilaksanakan di Dusun Pagaden,
Desa Margajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang.
Kegiatan ini dilakukan dari tanggal… 2014 sampai tanggal ….
2014
a) Waktu Kegiatan
Kunjungan ke-1
Hari/ Tanggal : Sabtu, 14 November 2014
Pukul : 09.00 – 11.30
Kunjungan ke-2
Hari/ Tanggal : Sabtu, 14 November 2014
Pukul : 09.00 – 11.30
Kunjungan ke-3
Hari/ Tanggal : Sabtu, 25 November 2014
Pukul : 10.00 – 16.00
b) Lokasi Kegiatan
Tempat : Desa Margajaya, Kecamatan Tanjungsari,
Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
3.2. Desain Penelitian
Dalam kegiatan survei lapangan yang kami laksanakan,
kami menggunakan metode pendekatan RRA (Rapid Rural
Appraisal) yang merupakan salah satu teknik alternatif
untuk melakukan suatu survei dengan metode konvensional,
karena metode ini relatif cepat melakukan suatu penilaian
dimasyarakat setempat, mengenai kebutuhan ataupun potensi
masyarakat dengan tujuan menentukan suatu strategi tertentu
untuk memecahkan masalah yang terjadi.
RRA dapat berupa interview, fokus grup, pertemuan,
observasi, penelitian kecil, dan analisis data. Kegunaan
dari teknik ini untuk mengidentifikasi mitra potensial
dalam pengelolaan sumberdaya, dan untuk menggali pendekatan
yang tepat sesuai dengan karakteristik. Prinsip Rapid Rural
Appraisal:
• Data yang dikumpulkan harus sangat relevan.
• Metode yang digunakan mengadaptasi kondisi lingkungan
setempat.
• Anggota dari komunitas dapat memberikan masukan terhadap
pendefinisian kebutuhan dan juga alternatif solusinya.
Kelebihan Rapid Rural Appraisal diantaranya:
Membutuhkan biaya yang relatif rendah, dapat dilaksanakan
dengan cepat, dimiliki oleh masyarakat setempat, fleksibel,
dapat mengidentifikasikan pemahaman dari isu yang kompleks,
multi bidang, dan memberikan dorongan bagi masyarakat
setempat. Dan kekekurangan dari Rapid Rural Appraisal
adalah: terbatas, pengambil keputusan harus menguasai
statistik, persiapannya membutuhkan waktu dan pelatihan skill
yang dibutuhkan misalnya: wawancara, komunikasi, dll
3.3. Proses Pengumpulan Data
Proses pengumpulan data yang dilakukan kegiatan kuliah
lapangan ini yaitu wawancara dan studi literatur. Wawancara
merupakan teknik untuk mendapatkan informasi dengan
melakukan tanya jawab langsung kepada petani yang berada di
Desa Margajaya sebagai narasumber. Studi lieratur dilakukan
untuk melengkapi hasil dari wawancara dengan melihat
beberapa referensi yang berkaitan dengan hal tersebut.
3.4. Metode Analisis Data (Deskriptif)
Dari hasil wawancara yang kami dapatkan dari petani
sebagai narasumber, di dapatkan hasil bahwa kondisi
pertanian di Dusun Pagaden, Desa Margajaya masih belum
sesuai dengan konsep LEISA. Dapat dilihat dari masih
banyaknya penggunaan bahan-bahan kimia untuk pupuk serta
pestisida walaupun penggunaan pupuk kandang sudah ada
sebagian yang melakukannya.
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian (Survei)
Desa Margajaya merupakan bagian dari wilayah Kecamatan
Tanjungsari, memiliki luas wilayah sekitar 230,5 Ha yang
berada di dataran rendah dengan ketinggian 890 dpl yang
terdiri atas 106 Ha sawah, 86,6 Ha lahan bukan sawah dan 3,7
lahan bukan pertanian.
Berdasarkan data tahun 2013 diketahui bahwa jumlah penduduk
Desa Margajaya berjumlah 10.618 orang yang terdiri dari 5.425
orang laki–laki dan 5.193 orang Perempuan.
Gambar 1. Peta Desa Margajaya
Batas – batas administratif pemerintahan Desa Margajaya
Kecamatan Tanjungsari sebagai berikut:
Sebelah utara : Desa Gudang
Sebelah Timur : Gunungmanik
Sebelah Selatan : Desa Raharja, Desa Cinanjung
Sebelah Barat : Desa Tanjungsari
Dilihat dari topografi dan kontur tanah, Desa Margajaya
Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang secara umum berupa
darat dan pesawahan dengan suhu rata – rata 190 s/d 250
Celsius. Desa Margajaya terdiri dari 5 (Lima) Dusun, 19
( sembilan belas ) Rukun Warga ( RW ) dan 50 ( Lima puluh )
Rukun Tetangga ( RT ).
Orbitasi dan waktu tempuh ibukota Kecamatan 2,2 km2 dengan
waktu tempu selama 20 menit dan dari ibukota kabupaten 20.5
dengan waktu tempuh 60 menit
Jarak dan letak Desa dari Ibu kota Pemerintahan :
Jarak ke Ibu Kota Kecamatan : 2,5 Km
Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 20,5 Km
Jarak ke Ibu Kota Propinsi : 42,5 Km
Jarak ke Ibu Kota Negara : 115 Km
4.2. Kedaan Penduduk Desa, Sosial Ekonomi, dan Kelembagaan
a) Mata pencaharian penduduk Desa Margajaya Kecamatan
Tanjungsari terdiri dari :
Petani :491 orang BuruhTani :735 orang Pedagang :495 orang PNS :245 orang TNI/Polri :147 orang KaryawanSwasta :392 orang Wirausahalainnya :694 orang Montir :31 orang Pengarajin Industri Rumah :72 orang
Tangga Peternak :187 orang Pembantu Rumah Tangga :73 orang
b) Tingkat Kesejahteraan
Jumlah Keluarga :
3188 KK
Keluarga prasejahtera :
306 KK
Keluarga prasejahtera I :
591KK
Keluarga prasejahtera II :
765 KK
Keluarga prasejahtera III
: 664 KK
Keluarga prasejahtera III plus
: 89 KK
c) Tingkat Pendidikan
Buta hurup : 6 jiwa
Tidak tamat SD/Sederajat : 61 jiwa
Tamat SD / Sederajat : 5213 jiwa
Tamat SLTP / Sederajat : 1274 jiwa
Tamat SLTA / Sederajat : 593 jiwa
D 1 : 118 jiwa
D 2 : 94 jiwa
D 3 : 83 jiwa
S 1 : 99 jiwa
S 2 : 49 jiwa
S 3 : 42 jiwa
d) Sarana da nPrasarana Ekonomi
Bank : - buah
Koperasi Unit Desa : - buah
Pasar : - buah
BUMDES : 1 buah
Industri Rumah
Tangga
: 15 buah
Perusahaan Kecil : 12 buah
Perusahaan Sedang : 6 buah
Perusahaan Besar : 1Buah
e) Kondisi Kesehatan dan Prasarana Kesehatan
Data kajian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di
Desa Margajaya adalah sebagai berikut :
Jumlah Rumah : 2998 Jumlah KK : 2210 Ibu Bersalin : 178 LINAKES : 163 Bayi< 6 bl : 105 ASI Saja : 78 Bayi 6-12 bl : 95 Lulus ASI Ekslusif : 71
Bayi dan Balita : 607 Ditimbang : 554 Pengguna Air Bersih : 2397 Cuci tangan dengan air
mengalir dan sabun
: 2396 Pengguna Jamban Sehat : 2397 Berantas Jentik nyamuk : 108 Makan sayur dan buah setiap
hari
: 108 Aktivitas fisik setiap hari : 2395 Tidak merokok dalam rumah : 788 Keluarga Sehat : 786 KeluargaTidak Sehat : 1424 Rumah Tangga Sehat : 662 Rumah Tangga Tidak Sehat : 1548 Persentase KK Sehat : 35.6 Persentase Rumah Tangga Sehat : 30
f) Sarana kesehatan yang ada di Desa Margajaya meliputi :
Puskesmas : - buah Puskesmas Pembantu : 1 buah Poskesdes : 1 buah Balai
Pengobatan/Klinik
: 2 buah
Dokter Umum : - orang Posyandu : 11 buah Pos KB Desa : 1 buah Bidan : 2 orang Petugas Gizi
Keliling
: 1 orang
Dukun Bayi terlatih : 3 orang
g) Sumber air bersih yang ada di Desa Margajaya meliputi :
Sumur Gali : 2.459 Buah PAM : 802
Embung : 10
4.3. Potensi Sumber Daya Alam Lokasi Survei (Kekayaan dan
Sifat Agoekosistem)
a) Keadaan Tanah, Penggunaan Tanah dan Kondisi Air
Keadaan tanah di desa margajaya sebagian besar berwarna
kuning, tekstur debuan, dengan kedalamam 0,50 m. Sebagan
besar tanah digunakan untuk perumahan rumah-rumah warga),
sisanya yaitu pertanian, perkebunan, kehutanan,
peternakan, dan perikanan.
Kondisi Air sangat baik, terdiri dari prasarana air
bersih dengan menggunakan sumur pompa 1140 unit, sumur
galian 855 unit, jumlah mata air 3 unit dan tempat umum
25 unit. Sedangkan jumlah irgasi terdiri dari 1 pembagi
air dengan kondisi rusak.
b) Peternakan/Perikanan/Pertanian
Jenis populasi ternak di Desa Margajaya terdiri dari
375 ekor ayam, 300 ekor bebek, 1 ekor kuda, dan 60 ekor
Biri-biri. Dimana produksi peternakan nya terdiri dari
: telur 360 kg/tahun, dan Daging 240 kg/tahun.
Jenis potensi dan produksi ikan terdiri dari ikan mas,
ikan lele, ikan nila dan ikan gurame. Dimana setiap
tahunnya Desa Margajaya dapat menghasilkan Ikan Mas
6000 kg/tahun, Ikan Lele 300 kg/tahun, Ikan Nila 4000
kg/tahun, dan Ikan Gurame 200 kg/tahun.
Lahan pertanian yang dimiliki oleh Desa Margajaya
sangat minim, sehingga aktivitas pertanian jarang
ditemukan di sana. Luas lahan pertanian menurut
komoditas pada tahun ini adalah 1 ha, yang digunakan
untuk menanam Ubi Kayu.
4.4.1. Pelaksanaan Sistem Pertanian/Sistem Usahatani di
Lokasi Survei dengan Komoditas Jagung
Teknik budidaya LEISA
Teknik bidaya LEISA yang dikembangkan di Dusun
Pagaden yaitu dengan memanfaatkan sumberdaya lokal
diantaranya yaitu pemakaian pupuk kandang dan pupuk urea
yang berimbang digunakan dalam pertanaman. Pupuk kandang
yang biasa digunakan yaitu berasal dari kotoran ayam dan
sapi. Pupuk kandang kotoran ayam didapat dari ternak yang
dikembangkan oleh petani Dusun Pagaden. Kotoran ini
mengandung unsur hara lengkap yang dibutuhkan tanaman.
Pupuk kandang mengandung unsur hara makro dan mikro.
Pemakaian kotoran sapi di desa ini bukan hanya
digunakan sebagai pupuk kandang saja, namun sebagai
pembuatan biogas. Letaknya berada di Dusun Ciluluk yang
dikembangkan oleh Kelompok Tani Pagaden. Kelompok Tani
Pagaden memiliki sepuluh ekor sapi yang diternakan untuk
dimanfaatkan kotorannya sebagai bahan biogas yang
ditempatkan di rumah-rumah warga. Namun, hasil ampas dari
biogas tersebut belum maksimal dimanfaatkan kembali untuk
pupuk kandang.
Pola tanam (kecocokan)
Curah hujan Kecamatan Jatinangor tahun 2009
Letak Dusun Pagaden yang berada di dataran medium
dengan udara yang tidak terlalu panas menyebabkan daerah
ini cocok untuk ditanam tanaman pangan. Karena daerah ini
didominasi oleh lahan kering yang hanya memanfaatkan air
hujan untuk pengairan, maka dalam satu tahun pola tanam
biasa dilakukan pada musim hujan saja. Ciri khas
pertanian di wilayah Desa Margajaya ini adalah pola tanam
jagung dengan sistem tumpang sari.
Tumpang sari yang biasa dilakukan yaitu :
a) Jagung – singkong
Gambar 4.2 Petani dengan lahan jagung dan singkong.
Jagung dan singkong ditanam di areal seluas 200 m2.
Jarak tanam pada pertanaman ini yaitu 60x60 cm2.
Berikut merupakan pola tanam dan kalender tanam
pertanaman tumpang sari jagung-singkong:
Gambar 4.3 Kalender Tanam Jagung – singkong:
JAN FEB MAR APR MEI JUN JU
L
AGU SE
P
OKT NOV DES
J. 1 J. 2 BERA J. 1S. 1 BERA S. 1
Keterangan :
J. 1 : Masa pertanaman jagung ke-1
J. 2 : Masa pertanaman jagung ke-2
S. 1: Masa pertanaman singkong ke-1
Gambar 4.4. Pola Tanam Jagung – singkong:
Keterangan:
X : Singkong
V : Jagung
Tumpang sari yang dilakukan oleh beberapa petani
diakukan hanya sekedar memanfaatkan lahan yang
berjarak, bukan dijadikan komoditas utama. Tanaman
singkong dijadikan tanaman tumpang sari karena
budidayanya yang mudah dan produktivitas yang banyak.
b) Jagung – singkong – kacang merah
Gambar 4.5 Lahan pertanman jagung-singkong-kacang
merah.
Pertanaman jagung – singkong – kacang merah yang
terdapat di salah satu areal Desa Margajaya biasa
ditanam di luas lahan sebesar 1 ha. Berikut merupakan
pola tanam dan kalender tanam pertanaman tumpang sari
jagung-singkong-kacang merah:
Gambar 4.6 Kalender Tanam Jagung – singkong:
JAN FEB MAR APR MEI JUN JU
L
AGU SE
P
OKT NOV DES
J. 1 J. 2 BERA J. 1KM. 1 KM. 2 BERA KM. 1
S. 1 BERA S. 1
Keterangan :
J. 1 : Masa pertanaman jagung ke-1
J. 2 : Masa pertanaman jagung ke-2
S. 1 : Masa pertanaman singkong ke-1
KM. 1 : Masa pertanaman kacang merah ke-1
KM. 2 : Masa pertanaman kacang merah ke-2
Gambar 4.7 Pola Tanam Jagung – singkong – kcang merah:
Pada penanaman jagung, dibutuhkan 2 benih/lubang tanam
sedangkan untuk kacang merah dibutuhkan 1 lbenih/lubang
tanam. Umur tanaman singkong adalah yang paling lama
yaitu 8 bulan, sedangkan jagung membutuhkan waktu 3,5
bulan, dan kacang merah sekitar 70 hari. Tanaman jagung
mengalami dua kali masa panen selama setahun. Setelah
memasuki musim kemarau, lahan diberakan karena tidak ada
pasokan pengairan.
Produktivitas
Total produksi jagung yang dihasikan di Desa
Margajaya rata-rata 200 kwintal/kg benih per luasan lahan
sebesar 1 ha. Pada kacang merah dihasilkan sebanyak
7,5kg/1 takaran.
Pemasaran
Hasil produksi jagung sebagian besar dijual ke
bandar untuk didistribusikan ke Jakarta dan Bandung.
Sedangkan pada singkong, produksi dikonsumsi oleh warga
sekitar dan langsung dibeli bandar penjual tape keliling
di sekitar Desa Mrgajaya.
Kendala
Masih banyaknya pemakaian bahan kimia pada pertanian di
Desa margajaya.
Kurangnya pengetahuan para petani mengenai pertanian
organik.
Tidak adanya kelompok tani khusus Desa Margajaya
sendiri.
Kurangnya penyuluhan ke petani di pelosok desa.
Adanya korupsi pada sistem di kelompok tani yaitu
mengomersilkan produk bantuan dari pemerintah.
Rangkuman Hasil Analisa
Tanaman jagung merupakan komoditas utama Dusun
Pagaden. Tanaman jagung ini ditanam monokultur dan
tumpang sari dengan singkong atau kacang merah. Karena
lahan di dusun ini merupaka lahan kering, maka petani di
dusun ini menggantungkan hidup dari pertaniannya hanya
pada saat musim penghujan saja karena lahan hanya diairi
selama musim penghujan saja dan pada saat musim kemarau
lahan diberakan. Dalam penanamannya, petani sudah banyak
yang menggunakan pupuk kandang sebagai input namun masih
dikombinasikan dengan pupuk kimia. Kurangnya pengetahuan
petani mengenai pertanian organik menjadi suatu kendala
dalam mencuptakan sistem pertanian berkelanjutan.
Sosialisasi mengenai pertanian berkelanjutan perlu
digalakan melalui berbagai penyuluhan di desa ini.
BAB V
RANCANGAN MODEL SISTEM PERTANIAN BERKELANJUTAN (SPT) DI LOKASI
SURVEI
Rancangan Model Sistem Pertanian Berkelanjutan (SPT) Di Dusun
Pagaden, Desa Margajaya (Netta Eka Safitri) komoditas padi
gogo lahan kering
Pola tanam yang diterapkan di Dusun Pagaden, Desa
Margajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang pada
agroekosistem lahan kering dengan komoditas padi gogo adalah
padi-jagung-padi atau padi-jagung-bera. Luas lahan untuk lahan
kering padi gogo ini sekitar 200 tumbak dengan produktivitas
1,2 ton.
Penanaman padi dilakukan pada musim hujan yaitu sekitar
bulan desember sampai dengan maret lalu dilanjutkan dengan
penanaman jagung pada musim kemarau dan kemudian lahan kembali
diberakan atau ditanam kembali dengan padi. Penanaman sangat
tergantung dengan curah hujan yang tersedia.
Pengaturan pola tanam
Pola tanam yang diterapkan petani di Dusun Pagaden :
Rekomendasi :
Pada musim tanam pertama padi dapat ditanam karena
ketersediaan air pada musim hujan cukup berlimpah. Musim Tanam
kedua menanam jagung yang ditumpangsarikan dengan kacang tanah
untuk meningkatkan indeks pertanaman. Jagung termasuk tanaman
heavy feeders yaitu tanaman yang membutuhkan banyak unsur
nitrogen, sedangkan kacang tanah termasuk tanaman soil builders
yang dapat memasok unsur hara nitrogen untuk jagung. Pada
musim tanam ketiga dapat ditanam kembali dengan padi atau
dilakukan bera.
Penanaman padi dapat dilakukan dengan sistem tanam jajar
legowo. Penerapan sistem tanam jajar legowo karena adanya
keuntungan dan kelebihan yang lebih dibanding dengan sistem
tanam konvensional (tegel) diantaranya yaitu :
a. Adanya efek tanaman pinggir.
b. Sampai batas tertentu semakin tinggi populasi tanaman
semakin banyak jumlah malai persatuan luas sehingga
berpeluang menaikkan hasil panen.
c. Terdapat ruang kosong untuk pengaturan air, saluran
pengumpulan keong atau mina padi.
d. Pengendalian hama, penyakit dan gulma menjadi lebih mudah.
e. Dengan areal pertanaman yang lebih terbuka dapat menekan
hama dan penyakit.
f. Penggunaan pupuk lebih berdaya guna.
Pemanfaatan limbah bekas panen
jagung-kacang tanah
Pemupukan yang dilakukan oleh para petani di Dusun
Pagaden sebagian besar masih bergantung pada pupuk kimia,
walaupun penggunaan kompos sudah dilakukan namun hanya
sebagian kecil petani yang melakukannya. Pupuk kimia yang
sering digunakan adalah pupuk merek Ponska. Jerami bekas panen
biasanya dijual oleh para petani kepada para peternak,
seharusnya jerami bekas panen tersebut dapat digunakan kembali
sebagai bahan organic untuk pembenah tanah. Sekam dari hasil
panen pun bisa dimanfaatkan sebagai biochar.
Penggunaan benih varietas unggul
Para petani di Dusun Pagaden ini biasanya menggunakan
benih padi dari hasil penanaman pada musim sebelumnya, mereka
menggunakannya untuk dua sampai tiga kali penanaman. Padahal
seperti yang kita ketahui bahwa menanam dengan cara seperti
itu dapat menurunkan kualitas maupun kuantitas dari hasil padi
tersebut. Untuk itu, perlu dilakukannya penanaman benih unggul
yang bersertifikat yang sudah terjamin mutu serta kualitasnya
agar para petani dapat meningkatkan hasil produksi.
Penggunaan pestisida nabati dalam mengendalikan hama dan
penyakit
Para petani di Dusun tersebut masih menggunakan pestisida
sintetik dalam mengendalikan hama dan penyakit yang dapat
berdampak terjadinya pencemaran lingkungan dan jenuhnya tanah.
Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai penyuluhan dari
beberapa instansi terkait mengenai penggunaan pestisida
berbahan alami seperti sirsak, bawang putih, daun mimba dan
lain-lain yang juga efektif dalam mengendalikan berbagai hama
serta penyakit pada tanaman padi. Pestisida nabati juga lebih
ramah lingkungan dan pembuatannya cukup sederhana serta harga
yang relatif lebih murah.
Rancangan Model Sistem Pertanian Berkelanjutan (SPT) Di Dusun
Pagaden, Desa Margajaya (Shania Al Syamsi) komoditas padi gogo
lahan kering
Lahan kering yang ada Dusun Pagaden, Desa Margajaya,
Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang sebagian besar
ditanami dengan tanaman jagung, baik monokultur maupun
tumpangsari. Sebagian lainnya ditanami tanaman tahunan dan
padi gogo atau gogo rancah. Pola pertanaman padi gogo di lahan
yang kami survei adalah padi-jagung-padi atau padi-jagung-
bera, tergantung pada curah hujan. Luas lahan untuk lahan
kering padi gogo ini sekitar 200 tumbak dengan produktivitas
6kg/tumbak atau 1,2 ton.
Penanaman padi dilakukan pada musim hujan atau setelah
hujan turun beberapa kali yaitu sekitar bulan desember sampai
dengan maret. Selanjutnya pada bulan april ditanam jagung
sampai bulan juli. Pada bulan agustus lahan kembali diberakan
atau ditanam kembali dengan padi apabila curah hujannya cukup.
Penanaman yang dilakukan sangat tergantung dengan curah hujan
yang tersedia.
1. Pengaturan Pola TanamPola tanam yang sudah diterapkan :
Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov
PADI JAGUNG PADI/BERA
Rekomendasi Pola Tanam :
Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov
Padi + JagungKacang
Tanah/Kedelai
Kacang Tunggak/
Kacang Hijau
Pengaturan pola tanam yang dapat menutup tanah sepanjang
tahun merupakan tindakan konservasi tanah secara vegetatif
yang cukup efektif. Penggunaan sisa tanaman sebagai mulsa
sangat dianjurkan karena selain dapat mengurangi penguapan air
dari tanah atau menghambat kontak fisik air hujan ke butiran
tanah, juga dapat menambah kandungan bahan organik tanah yang
merupakan kunci keberhasilan pengelolaan lahan kering untuk
jangka panjang. Bila sisa tanaman digunakan kembali sebagai
mulsa, hasil tanaman tahun berikut dapat meningkat dan dapat
menekan penurunan keseburan tanah. Tanaman kacang-kacangan
juga dapat menambah kandungan hara didalam tanah dan membuat
tanah menjadi gembur.
Pengaturan pola tanam yang dianjurkan adalah : pada awal
musim hujan ditanami padi gogo karena lebih banyak kebutuhan
airnya, kemudian diikuti oleh tanaman palawija yang lebih
tahan kering. Pelaksanaannya setiap musim tanam dapat
dilakukan dengan sistem monukultur maupun tumpang sari. Tujuan
dari pola tanam tumpang sari ini adalah efisiensi penggunaan
sumberdaya seperti hara tanaman, air dan tenaga kerja,
mempertahankan kesuburan tanah serta menurunkan popolasi hama
dan penyakit.
2. Pemanfaatan Benih Varietas Uggul Lokal
Bebih padi gogo yang digunakan di Dusun Pagaden merupakan
benih padi dari hasil penanaman pada musim sebelumnya, benih
digunakan dua sampai tiga musim penanaman. Penggunaan benih
varietas unggul seharusnya sudah tidak dapat dipisahkan dari
sistem produksi pertanian terutama tanaman pangan yang masih
menggunakan benih sebagai satu-satunya sumber perbanyakan
tanaman. Penggunaan varietas unggul memang secara nyata dapat
meningkatkan hasil panen, namun pada dasarnya varietas unggul
merupakan varietas yang memiliki respon tinggi terhadap dosis
pemupukan tinggi sehingga apabila dikembangkan pada daerah
yang menggunakan input luar tingkat yang rendah, maka resiko
kerugian hasil panen akan menjadi lebih tinggi dibandingkan
dengan varietas lokal.
Untuk menunjang pertanian berkelanjutan yang menggunakan
faktor-faktor penunjang produksi (pupuk dan pestisida) dalam
jumlah minimal, maka diperlukan suatu perbaikan sistem
pengadaan benih ditingkat petani menuju pada sistem benih
unggul lokal yang lebih tahan terhadap kondisi lingkungan yang
kurang menguntungkan. Oleh karena itu ditingkat petani perlu
diarahkan untuk dapat mengelola sumberdaya genetik yang
dimiliki (varietas unggul lokal) dengan sebaik-baiknya, baik
dalam hal konservasi varietas, penanganan, maupun penyimpanan
benih hingga benih siap digunakan.
Konservasi semacam ini sangat penting dilakukan sebagai
suatu pendekatan yang berorientasi pada petani dalam memasok
benih. Suatu pendekatan yang dapat diupayakan dalam
pengelolaan sumberdaya genetik adalah pembentukan unit-unit
suplai benih yang dibuat dengan cara membentuk unit-unit
pertanian kecil untuk memproduksi benih unggul yang cukup
memadai untuk kebutuhan lokal. Tentu saja para petani tersebut
memerlukan arahan dari unit-unit inspeksi benih terpusat. Jika
petani telah terbiasa dengan teknik tersebut, mereka dapat
mengambil alih perawatan penangkaran hingga akhirnya menjadi
yayasan benih yang bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Pengadaan
benih dapat dilakukan pada tingkat desa dengan teknik-teknik
yang bersifat padat karya sehingga mengurangi biaya
transportasi, yang sekarang menjadi bagian utama yang
menentukan harga benih. Apabila sistem ini telah berjalan
dengan baik maka kebutuhan petani terhadap 4 (empat) tepat
benih ( tepat mutu, jumlah, waktu, dan harga) dapat terpenuhi.
3. Komplementari Hewan Ternak dan Tanaman Pangan
Integrasi sumber-sumber hewan ternak dan tumbuhan untuk
memperoleh output biomassa yang optimal dalam lingkungan
ekologi dan sosio-ekonomi tertentu harus menjadi tujuan dalam
sistem pertanian berkelanjutan. Interaksi yang sesuai diantara
komponen-komponen harus menghasilkan respon komplementari
(saling melengkapi) dan sinergetik sehingga dapat mendorong
peningkatan efisiensi produksi dan memperkuat viabilitas
ekonomi dari sistem pertanian yang terpadu.
Sistem produksi ternak herbivora yang dikombinasi dengan
lahan-lahan pertanian dapat disesuaikan dengan keadaan tanaman
pangan. Ternak tidak berkompetisi pada lahan yang sama.
Tanaman pangan adalah komponen utama dan ternak menjadi
komponen kedua. Ternak dapat digembalakan di pinggir atau pada
lahan yang belum ditanami dan pada lahan setelah pemanenan
hasil sehingga ternak dapat memanfaatkan limbah tanaman pangan
seperti gulma, rumput, semak dan hijauan pakan yang tumbuh
disekitar tempat tersebut. Sebaliknya ternak dapat
mengembalikan unsur hara dan memperbaiki struktur tanah
melalui urin dan fesesnya. Mott (1974) melaporkan bahwa dari
nitrogen tumbuhan dan mineral yang dimakan hewan di areal
penggembalaan, sekitar 75 – 95 persen nitrogen dan 90 – 95
persen mineral dikembalikan ke tanah. Contoh penerapan sistem
ini di Sumatra dilaporkan bahwa sumbangan ternak terhadap
total hasil usahataninya adalah sebanyak 17 persen, sedangkan
di Cina sebanyak 29 persen (Moningka, dkk., 1993).
4. Pengelolaan Hama Penyakit Terpadu
Petani di Dusun Pagaden pada umumnya menggunakan
pestisida sintetik, karena mereka menganggap bahwa dengan
penggunaan pestisida sintetik lebih ampuh untuk menangani
masalah serangan hama dan penyakit di lahan mereka. Tetapi
penggunaan zat kimia harus tepat dan bijaksana. Dalam konsep
pengendalian hama penyakit terpadu (PHT), penggunaan pestisida
ditujukan bukan untuk memberantas atau membunuh hama namun
lebih dititik beratkan untuk mengendalikan hama sehingga
berada di bawah ambang kendali.
Pengendalian hama terpadu adalah upaya mengendalikan
tingkat populasi atau tingkat serangan organisme terhadap
tanaman dengan menggunakan dua atau lebih teknik pengendalian
dalam satu kesatuan untuk mencegah atau mengurangi kerugian
secara ekonomis dan kerusakan lingkungan hidup. Perlindungan
tanaman dilakukan melalui kegiatan pencegahan, pengendalian
dan eradikasi.
Konsep pengelolaan hama terpadu ini sangat sesuai dengan
konsep yang diusulkan oleh Peterson pada tahun 1973 yaitu : 1)
Secara terpadu memperhatikan semua hama penting, 2) Tidak
bertujuan untuk mendapatkan suatu keadaan yang bebas hama,
tetapi untuk mengendalikan populasi hama agar kerusakan yang
terjadi selalu di bawah ambang ekonomi, 3) Menggabungkan
berbagai cara yang kompatibel. Sesedikit mungkin memakai cara
buatan (kimia) tetapi lebih mementingkan penekanan hama oleh
faktor-faktor alami, 4) Selalu didasari oleh pertimbangan
ekologi.
Pengelolaan penyakit pada pertanian berkelanjutan harus
didasari dengan kesadaran akan lingkungan, dan kesadaran akan
biaya. Jika kerusakan berat sekali dan semua usaha yang
dilakukan tidak memberikan hasil, maka tanaman tersebut lebih
baik diganti.
DAFTAR PUSTAKA
Desa Margajaya Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang.
2014. BUKU SEJARAH DESA DAN APARATUR DESA MARGAJAYA .
Putra, Sasongko. 2013. PERENCANAAN PERTANIAN BERKELANJUTAN DI
KECAMATAN SELO. Diakses dari: http://eprints.undip.ac.id/,
pada tanggal 15 Desember 2014.
Suhartin. PEMASYARAKATAN PERTANIAN ORGANIK SEBAGAI UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN DALAM PERTANIAN RAMAH LINGKUNGAN.
Diakses dari: http://staff.uny.ac.id/, pada tanggal 15
Desember 2014.
Mayrowani, Henny. 2010. OPTIMALISASI SUMBERDAYA PERTANIAN PADA
AGROEKOSISTEM LAHAN KERING. Diakses dari:
http://pse.litbang.pertanian.go.id/, pada tanggal 15
Desember 2014.
Mohammad Toha, Husin. PENGEMBANGAN PADI GOGO MENGATASI RAWAN
PANGAN WILAYAH MARGINAL. Diakses dari
http://www.litbang.pertanian.go.id/ , pada 16 Desember 2014