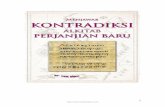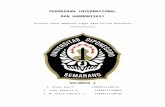Perjanjian Internasional
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Perjanjian Internasional
BAB I
PENDAHULUAN
1. Perkembangan Hukum Perjanjian Internasional Sebelum Berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Dalam perkembangan sejarah hubungan internasional, perjanjian yang dilakukan
antara negara mempunyai peranan yang sangat mendasar, apalagi perjanjian itu sendiri
merupakan sumber Hukum Internasional dan sekaligus sebagai cara bagi semua negara
untuk mengembangkan kerjasama yang damai meskipun sistem sosial dan konstitusinya
berbeda. Hal ini sejalan dengan tujuan United Nations dalam rangka menciptakan
keadaan dalam suasana yang adil dan menghormati kewajiban-kewajiban internasional
yang timbul dengan perjanjian antar negara tersebut.
Sebelum berdirinya United Nations, masalah perjanjian antar negara baik bersifat
bilateral maupun multilateral, dalam perkembangan kemajuan Hukum Internasional
masih belum dapat dikodifikasikan secara menyeluruh dan mendasar, karena itu di dalam
praktek pembuatan perjanjian antar negara pada masa itu masih didasarkan pada aturan-
aturan kebiasaan internasional. Mengenai mekanisme untuk membentuk aturan-aturan
baru dalam Hukum Internasional adalah sangat terbatas. Kebiasaan tersebut hanya
mengandalkan pada tindakan dalam praktek negara yang didukung oleh ‘Opinio
Jurist’,walaupun tidak selalu, biasanya merupakan suatu proses yang berkembang dan
tepat pada waktunya.
Perjanjian itu di lain pihak merupakan cara yang lebih bersifat langsung dan
formal dalam pembentukan Hukum Internasional. Negara melakukan kegiatan-kegiatan
yang sangat banyak dengan menggunakan perjanjian itu sebagai alat walaupun dirasakan
kurangnya prosedur di dalam Hukum Internasional. Sedangkan kenyataannya ada banyak
cara, di mana subyek dalam perundang-undangan nasional sesuatu negara dapat
membuat hak dan kewajiban yang mengikat. Sebagai contoh, suatu peperangan akan
diakhiri, pertikaian akan diselesaikan, wilayah akan diduduki/didapat, kepentingan-
kepentingan khusus telah ditentukan, suatu persekutuan dibentuk dan suatu organisasi
internasional didirikan, yang semuanya itu dibuat dengan menggunakan perjanjian.
1
Karena itu konsep tentang perjanjian dan pelaksanaannya menjadi faktor yang sangat
penting bagi perkembangan Hukum Internasional.1
Dengan adanya perjanjian dan bentuk persetujuan internasional lainnya tersebut
telah merupakan kenyataan yang tercatat dalam sejarah. Sejak masa Grotius ( Hugo de
Groot) sampai masa-masa sesudahnya hal itu telah merupakan kebiasaan bagi negarawan
untuk menggunakan aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan yang bersifat
kontraktual antara individu-individu secara tersendiri dalam mengembangkan aturan-
aturan Hukum Internasional yang mengatur perjanjian antar negara. Kemudian setelah
beberapa dekade terdapat usaha untuk merumuskan aturan-aturan Hukum Internasional
tersebut. Walaupun usaha-usaha yang dirintis itu masih dalam tahap rancangan tentang
prinsip-prinsip umum, dalam prakteknya telah diterapkan oleh negara sebagai
keseragaman yang diharapkan dapat mendorong usaha kodifikasi Hukum Perjanjian
Internasional di masa berikutnya. Usha-usaha itu telah dapat dibuktikan dengan adanya
Konvensi Havana mengenai Perjanjian pada Tahun 1928 dan Harvard Research in
International Law yang menghasilkan suatu “Rancangan Konvensi tentang Hukum
Perjanjian” pada Tahun 1935.2
Namun, usaha-usaha tersebut dianggap kurang bersifat menyeluruh di bidang
Perjanjian Internasional, karena itu dianggap perlu dan mendesak bagi United Nations
untuk segera melakukan kodifikasi dan pengembangan kemajuan Hukum Perjanjian
Internasional guna membina perdamaian dan keamanan internasional dan
mengembangkan hubungan bersahabat serta tercapainya kerjasama antar negara.
Kebutuhan yang sangat mendesak dari masyarakat United Nations tersebut juga didasari
adanya dua pengalaman yang penting, yaitu, pertama adanya kesulitan dari negara yang
akan menyampaikan instrumen ratifikasi terhadap Perjanjian Multilateral dengan
“keberatan-keberatan”, “pensyaratan-pensyaratan” atau “Reservations”, dan ke dua,
keikutsertaan negara-negara baru dalam Perjanjian Multilateral Umum (General
Multilateral Treaties) yang dibuat di bawah naungan Liga Bangsa Bangsa (League of
Nations) yang sudah ada sebelum United Nations terbentuk.
a. Ratifikasi Perjanjian Multilateral dengan “Reservations”
1 Shaw MN, International Law, Second Edition, 1986, p.458.2 Lihat Fenwick CG, International Law, Fourth Edition, 1965, p.514-549, lihat juga Glahn Gv, Law among Nations, An Introduction to Public International Law, Second Edition, 1970,p.420.
2
Masalah “keberatan” terhadap Perjanjian Multilateral menjadi persoalan yang
praktis pada waktu “The General Assembly” dalam Tahun 1950 menghadapi masalah
“Keberatan” terhadap konvensi Mengenai Pencegahan dan Penghukuman Terhadap
Kejahatan Genosida”3 meminta kepada International Court of Justice untuk
memberikan pendapatnya tentang akibat “keberatan” terhadap konvensi dan dalam
waktu yang bersamaan juga telah menyerukan kepada International Law Commission4
untuk mempelajari masalah umum dari sudut pandang kodifikasi dan pengembangan
kemajuan Hukum Internasional.5
International Court of justice kemudian memberikan jawaban yang dianggap
masih menyangsikan yaitu dengan mengusulkan agar setiap pihak konvensi
mempertimbangkan bahwa negara yang membuat “keberatan” merupakan pihak
terhadap konvensi tersebut, apabila “keberatan” itu menurut pendapatnya adalah
sesuai dengan maksud dan tujuan konvensi itu, yaitu dengan membuat keputusan
tersendiri dengan negara tertentu.6 International Court of justice telah berpedoman
pada praktek yang telah ada pada Sekretaris Jenderal United Nations, bahwa suatu
“keberatan” yang dinyatakan sah haruslah diterima oleh para pihak yang membuat
perjanjian.7
General assembly kemudian mengakhiri persoalan tersebut dengan
mengesahkan suatu Resolusi yang meminta kepada Sekretaris Jenderal United
Nations untuk tetap berlaku sebagai depositor dari semua dokumen yang berisi
“keberatan-keberatan” itu kepada negara-negara yang berkepentingan dan
menyerahkannya kepada setipa negara untuk menarik konsekuensi hukum dari
penyampaian itu.8
b. Keikutsertaan Negara-Negara Baru Dalam Perjanjian Multilateral Umum.
3 yang disetujui oleh General Assembly pada tanggal 9 Desember 194 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 8 dan telah berlaku tanggal 12 Januari 1951.4 Untuk mengembangkan Hukum Internasional secara progresif, maka The General Assembly of the United Nations dalam sidangnya yang ke dua pada Tahun 1947 mengeluarkan sebuah Resolusi Nomor 174/II tentang Pembentukan “International Law Commission” didasarkan pada ketentuan Pasal 13 ayat 1 butir a-Charter of the United Nations yang berbunyi :..promoting international cooperation in the political fields and encouraging the progressive development of International law and its codification.5 Fenwick CG, Ibid.p.528.6 UN Yearbook, 1951, p.820.7 Report of the International Law Commission, 1951, p.3-8.8 UN Yearbook, 1951, p.832.
3
Sehubungan dengan masalah keikutsertaan negara-negara baru sebagai pihak
pada Perjanjian Multilateral Umum tertentu yang dihasilkan semasa Liga Bangsa-
Bangsa, dalam Tahun 1962 General assembly pernah meminta kepada Komisi Hukum
Internasional9 untuk mempelajari masalah tersebut. Pada masa itu Dewan Liga
Bangsa-Bangsa telah diberikan otorisasi untuk mengundang negara-negara lainnya
sebagai tambahan untuk menjadi pihak dari perjanjian-perjanjian tersebut, tetapi bagi
negara-negara yang tidak diundang oleh Dewan sebelum dibubarkannya Liga Bangsa-
Liga Bangsa pada Tahun 1946 tidak dapat menjadi pihak karena tidak adanya
undangan untuk itu. Masalah tersebut pada mulanya oleh International law
Commission telah dimintakan perhatian dari General Assembly.
Dalam tahun yang sama dalam laporan International Law Commission kepada
General Assembly telah dinyatakan bahwa International law Commission telah
menemukan kesulitan dalam usaha mencari penyelesaian yang cepat dan memuaskan
terhadap masalah tersebut melalui jalur rancangan pasal-pasal mengenai Hukum
Perjanjian dan karena itu menyarankan untuk membicarakan kemungkinan
penyelesaian masalahnya lebih cepat dengan menggunakan prosedur yang lain seperti
langkah-langkah administratif.
Atas rekomendasi International law Commission maka General Assembly
telah mengeluarkan Resolusi 10 yang menetapkan bahwa General Assembly
merupakan badan yang paling layak untuk meneruskan tugas The League of Nations
sehubungan dengan adanya 21 Perjanjian Multilateral umum yang sifatnya Non
Politis atau teknis yang dihasilkan sewaktu berdirinya the League of Nations. Resolusi
itu juga minta kepada Sekretaris Jenderal United Nations mengenai beberapa hal:
a. Agar resolusi tersebut juga diberitahukan kepada pihak dari perjanjian-
perjanjian multilateral umum, tetapi mereka yang bukan anggota United
Nations;
b. Menyampaikan resolusi ini kepada negra-negara anggota yang menjadi pihak
dari perjanjian-perjanjian multilateral umum;
c. Mengadakan konsultasi jika perlu dengan negara-negara tersebut serta Badan-
Badan Khusus United Nations yang ada kaitannya denga masalahnya
mengenai apakah perjanjian-perjanjian multilateral umum yang tidak berlaku
9 Lihat Resolution of the General Assembly of the United Nations 1766 (XVII) tanggal 20 Nopember 1962 dan lihat pula “the Work of the International Law Commission, Fifth Edition, New York, 1996, p.56.10 Lihat Resolusi Majelis Umum PBB 1903 (XVIII) tanggal 18 Nopember 1963, lihat juga The Work of the International Law Commission, p.57-58.
4
lagi telah digantikan, atau tidak lagi ditawarkan kepada negara lain untuk
aksesi atau memerlukan tindakan lain untuk menyesuaikan dengan kondisi
seperti yang ada sekarang;
d. Melaporkan kepada General Assembly dalam sidang berikutnya mengenai
pelaksanaan resolusi ini;
e. Mengundang setiap negara anggota baik United Nations maupun Badan
Khusus United Nations atau yang menjadi pihak dalam Statuta International
Court of Justice ataupun yang telah dipercayakan dengan tugas-tugas General
Assembly dan yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi pihak dari
perjanjian yang dipersoalkan untuk melakukan aksesi dengan mendepositokan
satu instrumen aksesi kepada Sekretaris Jenderal United Nations.
Atas dasar resolusi tersebut, General Assembly kemudian menyatakan persetujuannya
terhadap 9 dari 21 perjanjian multilateral umum itu yang dapat diaksesi oleh negara-
negara lainnya yang berminat sebagai tambahan dan meminta perhatian dari para
pihak yang berkeinginan untuk mengesahkan beberapa perjanjian itu pada kondisi
seperti yang ada sekarang, khususnya dalam hal pihak-pihak yang baru akan
memintanya.11
2. Lingkup Perjanjian Internasional.
Mengenai lingkup dari permasalahan perjanjian internasional hampir tidak ada
batasnya karena menyangkut masalah politik, ekonomi, perdagangan, sosial,
kebudayaan, dan berbagai persoalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Daftar macam
perjanjian juga hampir tidak ada akhirnya dari perjanjian tentang Persekutuan Militer,
pengaturan Perlucutan Senjata, perilaku peperangan,, membuat perdamaian, jaminan
terhadap netralitas, penyelesaian sengketa, perbatasan, ekstradisi, hubungan
diplomatik dan konsuler, pelayaran dan lalu-lintas perkapalan, penerbangan, bea
cukai, hak cipta, perpajakan, imigrasi, kondisi perburuhan, kesejahteraan sosial,
pertukaran budaya, bantuan ekonomi dan teknik, masalah pengungsi, timbangan dan
ukuran, perhubungan dan topik-topik khusus lainnya.
Bagi kerjasama dan saling ketergantingan internasional memang diperlukan
bagi negara-negara untuk membuat ratusan perjanjian yang bukan saja mengatur
urusan mereka satu sama lain, tetapi juga untuk meningkatkan kepentingan dan 11 Lihat Resolution of the General Assembly 2021 (XX) tanggal 5 Nopember 1965.
5
kemudahan masing-masing. Seperti juga kontrak-kontrak dalam kehidupan domestik,
perjanjian benar-benar merupakan pokok dalam hubungan masyarakat internasional.12
Kemampuan untuk membuat perjanjian internasional adalah merupakan satu atribut
dari negara yang berdaulat.13 Suatu perjanjia pada dasarnya merupakan persetujuan
antara para pihak mengenai berbagai persoalan internasional. Meskipun perjanjian-
perjanjian itu dibuat antara negara dan organisasi internasional pada intinya juga
menyangkut hubungan antara negara. International Law Commission ternyata telah
dapat menyelesaikan seperangkat rancangan pasal-pasal mengenai perjanjian antar
negara dan organisasi internasional.14
Kemudian Konvensi Internasional mengenai Hukum Perjanjian telah
ditandatangani pada Tahun 1969 dan telah berlaku sejak Tahun 1980, karena itu maka
penekanannya pada aturan-aturan yang layak yang telah muncul diantara negara-
negara. Konvensi Wina mengenai Hukum Perjanjian 1969 sebagian memuat Hukum
Kebiasaan15 dan merupakan kerangka dasar bagi setiap pembicaraan mengenai sifat
perjanjian.
3. Fungsi Dan Tujuan Perjanjian Internasional.
Dalam kehidupan masyarakat internasional dewasa ini, Perjanjian
Internasional mempunyai beberapa fungsi yang tidak bisa diabaikan. Fungsi
pentingnya telah mendapatkan pengakuan umum anggota masyarakat bangsa-bangsa.
Keadaan demikian tercermin pada masyarakat internasional yang tertuang dalam
Preambul Konvensi Wina Tahun 1969 mengenai Perjanjian Internasional. Peran
penting yang fundamental dari Perjanjian Internasional dalam sejarah hubungan
internasional tidak dapat dipungkiri lagi. Beberapa fungsi dan tujuan Perjanjian
Internasional adalah sebagai berikut :
a. Perjanjian Internasional merupakan sarana utama yang praktis bagi transaksi dan
komunikasi antar anggota masyarakat negara;
b. Perjanjian Internasional sebagai sumber Hukum Internasional, yang oleh keluarga
bangsa-bangsa telah diakui mempunyai posisi tertentu yang berkembang dengan
12 Tung, William, International Law in an Organizing World, New York 1968, p.327.13 PCIJ (1923) Seri A. No.1.14 Yearbook of the International Law Commission, 1982, Vol.II, Pt 2,p.9, lihat Shaw MN, p.458-459.15 Lihat Kasus Namibia, dalam ICJ Reports, 1971, p.16,47 dan Kasus Fisheries Jurisdiction, ICJ Reports, 1973, p.3, 18.
6
pesat. Sumber-sumber Hukum Internasional yang lain dewasa ini terbukti tidak
memiliki kemampuan seperti Perjanjian Internasional dalam menanggulangi
tuntutan yang semakin besar dari masyarakat internasional;
c. Perjanjian Internasional sebagai sarana pengembangan kerja sama internasional
secara damai telah menunjukkan hasil positif. Tidak terhitung lagi jumlah negara
di semua kawasan dunia telah mengadakan kerjasama antar negara melalui
perundingan internasional yang menghasilkan banyak Perjanjian Internasional.
d. Perjanjian Internasional sebagai media penyelesaian sengketa internasional.
Sengketa internasional yang bermunculan di berbagai bagian dunia tidak sedikit
yang diselesaikan dengan sarana Perjanjian Internasional;
e. Perjanjian Internasional merupakan alat kontrol bagi para peserta yang terlibat di
dalam melaksanakan isi perjanjian tersebut;
f. Perjanjian Internasional menjamin “kepastian Hukum” (Rechtzeikerheid) bagi
para pihak yang berkepentingan;
g. Perjanjian Internasional menimbulkan hukum (Law Making) bagi subyek, peserta
dalam Perjanjian Internasional yang bersangkutan.
7
BAB II
KODIFIKASI HUKUM PERJANJIAN16
A. Hukum Perjanjian Sebagai Topik Utama.
International Law Commission dalam sidangnya yang pertama Tahun 1949
telah menempatkan Hukum Perjanjian Internasional diantara topik-topik yang
dianggap cocok untuk kodifikasi. Karena pembahasan topik-topik lainnya maka
Komisi baru dapat membicarakan kembali topik Hukum Perjanjian pada Tahun 1953
dalam sidangnya yang ke lima dan kemudian dalam sidangnya yang ke enam Tahun
1954. Namun tidak ada kemajuan yang berarti yang diperoleh dari komisi karena
penggantian penggantian rappoteur khusus (special rapporteur) yang terjadi pada
saat itu.
Di dalam perkembangan lebih lanjut dalam lima sidangnya yang diadakan
antara Tahun 1956-1960, komisi telah menerima laporan-laporan yang cukup berhasil
dari rapporteur khusus yang menangani masalah Hukum Perjanjian dengan disertai
rancangan De Novo dan kemudian disusunnya dalam bentuk satu “Expository Code”
atau “Code of a General Character” dan belum dalam bentuk konvensi internasional.
Pada waktu itu Komisi ternyata baru dapat memusatkan pekerjaannya mengenai topik
Perjanjian Internasional pada sidangnya yang ke sebelas pada Tahun 1959 dan telah
berhasil mengesahkan sementara naskah yang terdiri dari 14 pasal termasuk
komentarnya. Pada waktu komisi melaporkan hasil kerjanya mengenai topik tersebut
kapada General Assembly dalam tahun yang sama, komisi juga telah menjelaskan
alasan-alasan keterlambatannya dengan menyatakan sebagai berikut :
“Secara singkat, hukum Perjanjian bukanlah dengan sendirinya tergantung dari perjanjian, tetapi merupakan bagian dari Hukum Kebiasaan Internasional secara umum. Pertanyaan bisa timbul apakah Hukum Perjanjian itu diwujudkan dalam suatu Konvensi Multilateral, tetapi beberapa negara tidak menjadi pihak atau menjadi pihak pada konvensi itu dan kemudian sesudahnya menolaknya, karena ternyata mereka akan atau tetap terikat pada ketentuan-ketentuan dari perjanjian tersebut sepanjang ketentuan-ketentuan itu memasukkan Hukum Kebiasaan Internasional de lege lata.
16 The Work of the International law Commission, 1996, p.58-63.
8
Tidak diragukan lagi kesulitan timbul bila suatu konvensi memasukkan aturan-aturan hukum kebiasaan internasional. Dalam praktek hal itu sering tidak menjadi masalah. Dalam hal Hukum perjanjian hal itu bisa menjadi masalah karena Hukum Perjanjian itu sendiri merupakan dasar dari kekuatan dan pengaruh dari semua perjanjian. Dengan pertimbangan-pertimbangantersebut maka jika diputuskan untuk memasukkan “Code” tersebut atau sebagian darinya dalam bentuk satu konvensi internasional, maka perumusan akan sangat berubah dan mungkin penghapusan dari beberapa pokok, yang sudah tentu diperlukan “.17
Dalam sidangnya yang ke tiga belas, International law Commission telah
merubah cara kerjanya dengan mempersiapkan rancangan pasal yang mampu untuk
dijadikan dasar bagi suatu Konvensi Internasional. Keputusan ini kemudian dijelaskan
lagi oleh Komisi dalam sidangnya yang ke empat belas sebagai berikut :
“Pertama, satu “Expository Code” bagaimanapun juga telah dirumuskan dengan baik, tidak dapat diwujudkan sebagai sesuatu yang efektif seperti satu konvensi untuk menggabungkan hukum, dan penggabungan Hukum perjanjian adalah penting sekali dewasa ini pada waktu banyak negara baru telah menjadi anggota masyarakat Internasional.
Kedua, Kodifikasi Hukum Perjanjian Internasional melalui suatu Konvensi Multikultural akan memberikan peluang bagi semua negara untuk ikut serta secaralangsung dalam perumusan hukum jika mereka menghendakinya, dan keikutsertaan mereka dalam pekerjaan-pekerjaan kodifikasi nampaknya bagi komisi sangat diperlukan agar hukum Perjanjian dapat ditempatkan sebagai dasar yang paling luas dan paling terjamin.18
B. Pengesahan Rancangan Pasal-Pasal.
Dalam sidang yang sama komisi telah berhasil mengesahkan satu rancangan
sementara yang terdiri dari 29 pasal mengenai kesimpulan, masa berlakunya dan
registrasi perjanjian serta memutuskan untuk menyampaikan rancangan tersebut
kepada pemerintah negara-negara anggota untuk memperoleh tanggapan. Dalam
membahas laporan komisi tersebut, dalam tahun yang sama General Assembly telah
memberikan rekomendasi kepada komisi untuk menerukan pekerjaannya tentang
hukum perjanjian dengan memperhatikan semua pandangan yang diketemukan dalam
sidang General Assembly oleh para delegasi negara anggota dari tanggapan tertulis
yang disampaikan oleh Pemerintah negara-negara anggota.19
17 Yearbook of the International law Commission, 1959, volume II, document A/4169, para. 1818 Ibid. 1962, volume II, document A/5209, para.17.19 Lihat Resolusi General Assembly of the United Nations 1765 (XVII) tanggal 20 nopember 1962.
9
Dalam tahun berikutnya Komisi tekah membahas laporan dari Rapporteur Khusus dan
kemudian mengesahkan lagi rancangan sementara yang terdiri dari 24 pasal meliputi
pembatalan, berakhirnya dan penangguhan perjanjian serta memutuskan seperti biasanya
untuk menyampaikan kepada pemerintah negara-negara anggota untuk mendpatkan komentar
mereka. Dalam sidangnya yang ke enam-belas Tahun 1964, komisi kemudian membahas lagi
laporan Rapporteur Khusus dan mengesahkan satu rancangan sementara dari 19 Pasal
berikutnya tentang penerapan, pengaruh, peninjauan kembali dan penafsiran perjanjian dan
dengan demikian lengkaplah sudah rancangan sementara mengenai topik itu. Bagian ke tiga
dari rancangan pasal-pasal ini juga dimintakan komentar dari pemerintah-pemerintah negara
anggota.
Pada sidangnya yang ke tujuh-belas komisi sudah mulai mengadakan tinjauan
kembali tentang rancangan pasal-pasal sehubungan dengan komentar yang ditrerima dan
pembicaraan dalam Komite VI (Komite Hukum) General Assembly di mana mayoritas
banyak dari wakil-wakil negara anggota menyepakati keputusan komisi untuk memberikan
kodifikasi terhadap Perjanjian Internasional dalam bentuk “Konvensi”. Di sidang
berikutnya, komisi telah selesai mempelajari rancangan pasal-pasal yang terdiri dari 75 pasal
termasuk komentar masing-masing. Pada waktu komisi menyampaikan laporannya kepada
General Assembly, komisi memberikan rekomendasi agar General Assembly
menyelenggarakan satu Konferensi Internasional yang Berkuasa Penuh (International
Conference of Plenipotentiaries) untuk mempelajari rancangan pasal-pasal yang dihasilkan
oleh komisi mengenai Hukum Perjanjian dan menyelesaikan satu Konvensi mengenai
masalah itu.20
Dalam penyusunan rancangan pasal-pasal, komisi memutuskan untuk membatasi
lingkup penerapan dari pasal-pasal tersebut untuk perjanjian-perjanjian yang dibuat antara
negara, tidak dimasukkan perjanjian-perjanjian antara negara dan subyek Hukum
Internasional lainnya (misalnya seperti Organisasi Internasional) dan antara subyek-subyek
lainnya tersebut. Komisi juga memutuskan untuk tidak memasukkan Persetujuan
Internasional yang bukan dalam bentuk tertulis. Disamping itu komisi juga memutuskan
bahwa rancangan pasal-pasal tersebut tidak memuat ketentuan apapun mengenai topik-topik
seperti: dampak pecahnya peperangan bagi perjanjian-perjanjian, suksesi negara dalam
kaitannya dengan perjanjian-perjanjian, masalah tanggung jawab internasional suatu negara
20 Yearbook of the International Law Commission, 1966, vol.II, document A/6309/rev.1.para.9-38
10
dalam hal gagalnya melaksanakan kewajiban suatu perjanjian, “most favoured nation
clause”, dan penerapan perjanjian yang diadakan untuk hak dan kewajiban yang harus
dilaksanakan atau dinikmati oleh individu-individu.
C. Penyelenggaraan Konferensi Internasional Berkuasa Penuh.
Atas rekomendasi komisi, maka General Assembly dalam sidangnya yang ke dua
puluh satu telah memutuskan untuk menyelenggarakan satu Konferensi Internasional
Berkuasa Penuh (International Conference of Plenipotentiaries) untuk membicarakan Hukum
Perjanjian Internasional dan untuk menggabungkan hasil yang dicapai oleh komisi dalam
suatu konvensi internasional dan instrumen-instrumen lainnya serupa itu jika dipandang
layak. General Assembly juga minta kepada Sekretaris Jenderal United Nations untuk
mengadakan sidang pertama pada awal 1968 dan sidang yang ke dua pada awal 196921.
Tahun berikutnya, General Assembly juga memutuskan untuk mengadakan sidang
pertama konferensi Perserikatan bangsa-Bangsa mengenai Hukum Perjanjian dalam bulan
Maret 1968 di Wina Austria22 (United Nations Conference on the Law of treaties). Atas dasar
ini, maka sidang pertama telah diselenggarakan pada tanggal 26 Maret sampai 24 Mei 1968
di kota Wina dan dihadiri oleh 103 negara termasuk para peninjau dari 13 Badan Khusus
Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Badan Antar Pemerintah lainnya. Sedangkan sidang
keduanya diselenggarakan di tempat yang sama dari tanggal 6 April sampai 22 Mei 1969 dan
dihadiri oleh 110 negara serta peninjau dari 15 badan Khusus dan Badan Antar Pemerintah.23
Akhirnya konferensi telha mengesahkan Konvensi Wina mengenai hukum Perjanjian
pada tanggal 23 Mei 1969 dengan perbandingan suara 76 negara menyetujui, satu negara
menyatakan menolak (Perancis) dan 19 negara lagi menyatakan abstain (termasuk semua
anggota Blok Soviet). Konvensi ini terdiri dari Mukadimah, 85 Pasal dan Satu lampiran.
Konvensi ini telah dibuka untuk penandatanganan pada tanggal 23 Mei 1969 dan diteruskan
sampai tanggal 30 Nopember 1969 di kementerian Luar negeri Austria dan setelah itu di
markas Besar perserikatan Bangsa-Bngsa di New York sampai tanggal 30 April 1970.
Penandatanganan tersebut dilakukan sambil menunggu ratifikasi. Konvensi terbuka untuk
aksesi oleh setiap negara yang bukan penandatangan, diperbolehkan menjadi pihak. Sejak
tanggal 27 januari 1980 konvensi itu telah mulai berlaku dan sampai tanggal 20 Oktober 2003
telah ada 96 negara yang telah menjadi pihak pada Konvensi.
21 Lihat Resolusi Majleis Umum PBB 2166 (XXI) tanggal 5 Desember 1966.22 Ibid, Resolusi 2287 (XXII) tanggal 6 Desember 1967.23 Lihat Official Records of the United Nations Conference on the Law of treaties, First Session (E.68.V.7), Ibid, Second Session E.70.V.6)
11
Disamping telah disahkannya Konvensi mengenai Hukum Perjanjian itu, konferensi
juga telah menyetujui dua Deklarasi dan lima Resolusi24:
a. Declaration on the Prohibition of Military, Political or Economic Coercion in the
Conclusion of Treaties:
b. Declaration on Universal Participation in the Vienna Convention on the Law of
Treaties:
c. Lima Resolusi yang dilampirkan pada Final Act of the Conference.25
D. Konvensi Perjanjian Antara Negara dan Organisasi Internasional dan Antara
Organisasi Internasional dan Organisasi Internasioanl.26
Setelah Konvensi tentang Perjanjian Antar Negara berhasil disahkan, maka
Komisi dalam masa kerja berikutnya menyiapkan rancangan perjanjian antara negara dan
organisasi internasional dan antara organisasi internasional dengan organisasi
internasional. Rancangan naskah konvensi ini diserahkan oleh Komisi kepada General
Assembly dan kemudian dengan Resolusi Nomor 39/86 Tahun 1984, tanggal 13
Desemebr 1984 General Assembly menyerukan kepada negara-negara anggota
Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelenggarakan konferensi di Wina dari tanggal
18 februari sampai 21 Maret 1986. Berdasarkan pada rancangan naskah konvensi hasil
karya Komisi tersebut, diadakanlah konferensi di Wina pada tanggal tersebut dengan
landasan pokok pembahasan hasil kara komisi. Pada tanggal 20 maret 1986 wakil=-wakil
para pihak yang mengadakan perundingan berhasil menyepakati naskah final konvensi
dan pada tanggal 21 Maret 1986 perjanjian itu terbuka untuk ditandatangani oleh semua
negara yang hadir dalam konferensi. Kemudian sebagaimana biasa kepada negara-negara
diberikan kesempatan untuk menyatakan persetujuan terikat pada konvensi. Selanjutnya
konvensi ini lebih dikenal dengan nama ”Konvensi Wina Tahun 1986 tentang Hukum
Perjanjian Antar Negara dan Organisasi Internasional dan antara Organisasi Internasional
dan Organisasi Internasional (The 1986 Vienna Convention on the Law of Treaties
24 United nations, The Work of the International Law Commission, Sixth Edition, Volume 1 p.158.25 Lihat Official records of the United Nations Conference on the Law of Treaties, First and second Sessions, Document of the Conference (United nations Publication, Doc.A/Conf.39/26.26 Baca pada I Wayan Parthiana, Hukum Perjanjian Internasional bagian 1 (Bandung: Mandar Maju, 2002),p.8-11.
12
between State and International Organisation and between International Organisation
and International Organisation), atau disebut juga Konvensi Wina 1986 .
Timbul pertanyaan, mengapa Hukum Perjanjian Internasional ini dipisahkan
pengaturannya di dalam masing-masing konvensi yang berbeda ? Menurut International
Law Commission Hukum Perjanjian Internasional yang tumbuh dan berkembang
sebelumnya dalam bentuk Hukum Kebiasaan Internasional bagian terbesar merupakan
kaidah-kaidah Hukum Perjanjian Internasional yang berkenaan dengan perjanjian antar
negara. Juga dalam prkateknya ternyata negara-negara lah yang paling banyak dan paling
sering mengadakan perjanjian internasional. Kaidah-kaidah Hukum Perjanjian
Internasional yang mengatur tentang perjanjian antar negara ternyata sangat luas ruang
lingkupnya. Sedangkan pada lain pihak, perjanjian antara negara dengan organisasi
internasional maupun antara organisasi internasional dan organisasi internasional dalam
beberapa hal memiliki karakteristik tersendiri yang tidak sama dengan perjanjian antara
negara dengan negara.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dipandang lebih tepat
jika Hukum Perjanjian Internasional yang mengatur perjanjian antara negara dengan
negara diatur dalam konvensi tersendiri. Demikian pula kaidah hukum Perjanjian antara
negara dan organisasi internasional dan perjanjian antara organisasi internasional dan
organisasi internasional diatur dalam suatu perjanjian tersendiri. Meskipun terpisah
dalam masing-masing konvensi, tidaklah berarti bahwa substansi dari ke dua konvensi
tersebut berbeda sama sekali, sebagian besar substansinya mengandung kesamaan.
Pertanyaan selanjutnya akan timbul, bagaimanakah pengaturan hukumnya
mengenai perjnjian-perjanjian internasional antara negara ataupun organisasi
internasional di satu pihak dengan subyek-subyek Hukum internasional lainnya ?
Demikian pula pengaturan tentang perjanjian antara subyek subyek Hukum Internasional
lainnya selain daripada negara dan organisasi internasional satu dengan lainnya ?
Sepanjang mereka ini memilikikapasitas untuk mengadakan perjanjian internasional dan
memang haknya untuk mengadakan perjanjian internasional diakui dan dijamin oleh
Hukum Internasional.,maka kaidah-kaidah hukum Perjanjia Internasional yang
mengaturnya adalah kaidah-Kaidah hukum Perjanjian Internasional yang berupa
Kebiasaan Internasional.
13
Ditinjau dari segi substansi kaidah-kaidah hukum dari ke dua konvensi tersebut
dapat dikatakan bahwa substansinya itu merupakan perpaduan secara harmonis antara
kaidah-kaidah hukum perjanjian internasional yang sebelumnya berbentuk hukum
Kebiasaan Internasional pada satu pihak dan kaidah-kaidah Hukum Perjanjian
Internasional yang sama sekali baru sebagai hasil pengembangan progresif dari Hukum
Internasional pada lain pihak. Di dalamnya terdapat kaidah-kaidah Hukum perjanjian
Internasional yang memang sebelumnya sudah ada dan berlaku sebagai hukum kebiasaan
internasinal yang diformulasikan kembali ke dalam pasal-pasal kovensi dan disamping
itu terdapat juga beberapa pasal yang merupakan hasil pengembangan progresif atas
kaidah-kaidah hukum Perjanjian Internasional.27
Dengan adanya dua konvensi tentang Hukum Perjanjian Internasional tidaklah
berarti bahwa kaidah-kaidah itu sudah semuanya tercakup ke dalam ke dua konvensi ini,
di luar ke dua konvensi masih terdapat kaidah-kaidah Hukum Perjanjian Internasional
yang antara lain berbentuk hukum kebiasaan Internasional, sepanjang tidak bertebtangan
dengan kaidah Hukum Perjanjian Internasional yang terdapat dalam ke dua konvensi;
kaidah-kaidah Hukum perjanjian internasional yang berbentuk Yurisprudensui, doktrin
atau pendapat sarjana ataupun yang berupa General principles of Law reqognized by
Civilized Nations, maupun yang berbentuk keputusan atau resolusi organisasi-organisasi
internasional. Dengan perkataan lain semua yang dikemukakan di atas itu merupakan
sumber hukum dalam arti formal dari hukum perjanjian internasional.28
E. DEFINISI DAN PENGERTIAN PERJANJIAN INTERNASIONAL.29
1. Pengertian Perjanjian Internasional.
27 Inilah merupakan salah satu bukti bahwa antara kegiatan pengkodifikasian Hukum Internasional dengan pengembangan progresif Hukum Internasional seperti ditegaskan dalam Pasal 13 ayat 1 butir a Piagam PBB, walaupun secara teoritis dapat dibedakan pengertiannyam tetapai secara praktis ternyata sukar untuk dibedakan, apalagi dipisahkan. Lihat dan bacalah ulasan Mochtar Kusumaatmadja dalam MASALAH LEBAR LAUT TERRITORIAL PADA KONFERENSI-KONFERENSI HUKUM LAUT DI JENEWA 1958 DAN 1960, DISERTASI, Penerbit PT Universitas , Bandung, Thn.1962, hlm.13-17.28 Bandingkan dengan sumber-sumber Hukum Internasional pada umumnya, yang terdiri atas perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab, putusan badan-badan peradilan atau yurisprudensi, doktrin atau pendapat para sarjana, dan putusan atau resolusi organisasi-organisasi internasional. Semuanya ini adalah juga merupakan sumber hukum dalam arti formal dari Hukum Perjanjian Internasional, sebab pada hakekatnya Hukum Perjanjian Internasional itu adalah hanya salah satu bagian atau salah satu bidang saja dari Hukum Internasional pada umumnya.29 Lihat Satow’s Guide to Diplomatic Practice, Fifth Edition, New York, 1979, Bab 29.
14
Di zaman modern, perjanjian internasional telah merupakan sumber Hukum
Internasional yang sangat penting. Bila Mahkamah Internasional harus memutuskan
satu perselisihan internasional, upaya pertama adalah untuk menemukan apakah ada
perjanjian internasional apa tidak. Dalam hal terdapat suatu perjanjian yang mengatur
persoalan yang disengketakan, keputusan Mahkamah akan didasarkan pada
ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut. Perjanjian internasional menempati
posisi sama yang penting di dalam bidang Hukum Internasional sebagaimana
perundang-undangan di dalam hukum nasional.
Perjanjian Internasional adalah suatu persetujuan antara dua negara atau lebih
di mana mereka membina atau mencari hubungan yang diatur oleh Hukum
Internasional. Menurut pandangan Oppenheim, perjanjian internasional adalah
persetujuan yang bersifat kontraktual antara negara atau organisasi negara yang
menimbulkan hak dan kewajiban secara hukum bagi para pihak.30 Lain halnya
pendapat Schwarzenberger yang mendefinisikan, perjanjian adalah persetujuan
diantara subyek Hukum Internasional yang menimbulkan suatu kewajiban yang
mengikat di dalam Hukum Internasional, sedangkan menurut Starke, dalam hampir
semua kasus obyek perjanjian adalah untuk mengenakan kewajiban yang mengikat
pada negara-negara yang menjadi pihak pada perjanjian tersebut.31
Dalam rancangan sementara yang dibuat oleh Komisi Hukum Internasional,
telah memberikan definisi tentang Perjanjian Internasional sebagai berikut:
“Setiap persetujuan internasional dalam bentuk tertulis apakah yang terhimpun dalam satu instrumen atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun juga bentuknya (perjanjian, konvensi, protokol, covenant, piagam, statuta, akta, deklarasi, concordat, pertukaran nota, agreed minute, memorandum persetujuan, modus vivendi atau sesuatu sebutan lainnya) yang dibuat antara dua negara atau lebih atau subyek Hukum Internasional lainnya yang diatur oleh Hukum Internasional.
Mengenai pencantuman subyek hukum “Internasional lainnya” dimaksudkan untuk memberi peluang terhadap perjanjian yang dibuat oleh organisasi internasional, Takhta Suci Vatikan dan kesatuan internasional lainnya.
Di dalam Konvensi Wina Tahun 1969 mengenai Hukum Perjanjian seperti terlihat
dalam rancangan akhir yang disusun oleh Komisi Hukum Internasional, ketentuan-
30 Oppenheim L, International law, vol.1, Eight Edition, hlm.877, lihat pula Fawett JES, The Law of Nations, London, 1968, hlm.89.31 Starke, JG, An Introduction to International Law, Eight Edition (1977), hlm.459.
15
ketentuan dibatasi pada perjanjian-perjanjian antar negara (Pasal 1). Di dalam Pasal 3
dinyatakan bahwa Konvensi Wina Tahun 1969 tidak berlaku bagi persetujuan
internasional yang dibuat oleh negara-negara dan subyek Hukum Internasional lainnya
atau antara subyek Hukum Internasional yang lain tersebut atau bagi persetujuan
internasional yang bukan dalam bentuk tertulis tidak akan berpengaruh terhadap kekuatan
hukum persetujuan-persetujuan semacam itu. Sedangkan Pasal 2 (1) (a) Konvensi Wina
1969 memberikan definisi bahwa suatu perjanjian seperti juga persetujuan internasional
yang dibuat oleh negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh Hukum Internasional,
apakah tersusun dalam satu instrumen, dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan
apapun bentuknya yang dibuat secara khusus. Ketentuan ini memberi peluang pada
masalah tentang stattus atau kedudukan persetujuan yang dibuat antar negara dan individu-
individu serta badan hukum secara tersendiri dan yang diatur dalam hukum nasional.
2. Definisi Perjanjian Internasional.
Pasal 2 (1) (a) Konvensi Wina 1969 memberikan definisi suatu perjanjian,
untuk maksud konvensi tersebut sebagai berikut :
“Treaty means an international agreement concluded between states, in written form and governed by International Law, wether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation. (Perjanjian artinya suatu persetujuan internasional yang diadakan antara negara-negara dalam bentuk yang tertulis dan diatur oleh Hukum Internasional baik yang berupa satu instrumen tunggal atau berupa dua atau lebih instrumen yang saling berkaitan tanpa memandang apapun juga namanya).
Definisi ini tidak memasukkan persetujuan antara negara yang diatur oleh hukum
nasional dan persetujuan antar negara yang sama sekali tidak dimaksudkan untuk
menciptakan hubungan secara hukum. Tidak dimasukkannya ke dua jenis persetujuan ke
dalam definisi perjanjian jelas merupakan hal yang sudah biasa, tetapi definisi yang
diberikan di dalam Konvensi Wina 1969 sejauh itu dianggap lebih kontroversial, karena
tidak memasukkan persetujuan lisan antara negara dan persetujuan dari jenis apapun
antara organisasi internasional atau antara dengan organisasi internasional.32
Definisi perjanjian dalam konvensi Wina 1969 sengaja tidak memasukkan persetujuan
internasional yang dibuat antara negara dan organisasi internasional atau diantara
32 Peter Malanczuk, Modern Introduction to International Law, Seventh Edition, Akehurst’s, hlm.130-131.
16
organisasi internasional sendiri33 dan tidak juga memasukkan persetujuan internasional
tidak dalam bentuk ertulis. Komisi Hukum Internasional yang menyiapkan rancangan
pasal-pasal mengenai Hukum Perjanjian sebagai dasar pekerjaannya untuk pengembangan
kemajuan dan kodifikasi yang dicantumkan dalam Konvensi Wina mengenai Hukum
Perjanjian menjelaskan bahwa definisi tentang istilah Perjanjian yang diusulkan sama
sekali bukan dimaksudkan untuk menyangkal bahwa subyek hukum internasional lainnya
seperti organisasi internasional, kelompok pemberontak, boleh saja membuat perjanjian
sama halnya dengan Komisi hukum Internasional yang menjelaskan bahwa pembatasan
istilah perjanjian dan persetujuan internasional yang dinyatakan dalam tulisan bukanlah
dimaksudkan untuk menyangkal kekuatan hukum dari persetujuan lisan yang dibuat di
bawah hukum Internasional.34
Definisi yang diberikan oleh Mc.Nair lebih luas dibandingkan dengan Konvensi Wina
1969 karena dengan memasukkan persetujuan internasional yang dibuat antara negara dan
organisasi internasional, atau diantara organisasi internasional sendiri, tetapi definisi
tersebut tidak memasukkan persetujuan yang tidak dalam bentuk tertulis. Tentu saja
Mc.Nair menyadari khususnya bahwa meskipun hal itu jarang untuk menemukan
persetujuan lisan yang dibuat diantara negara, tidak bisa dikatakan bahwa hukum
internasional menganggap bentuk tertulis itu merupakan hal yang penting untuk
pembuatan suatu persetujuan antar negara35 Dalam hal ini Mc.Nair merujuk pada
Keputusan Permanent Court of International Justice (PCIJ) dalam kasus “Legal Status of
Eastern Greenland” dalam Tahun 1933 tatkala PCIJ harus membicarakan arti hukum dari
“suatu pernyataan lisan” yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri Norwegia M.Ihlen yang
ditujukan kepada Duta Denmark yang ditempatkan di Norwegia. PCIJ menyimpulkan
sebagai berikut :
“Bahwa satu jawaban seperti ini yang diberikan oleh Menteri Luar Negeri atas nama pemerintahnya untuk menjawab permintaan dari wakil diplomatik dari negara lain, mengenai masalah yang ada di bawah bidang wewenangnya, adalah mengikat pada negara di mana Duta itu berasal.”36
Mahkamah Internasional juga pernah membicarakan seberapa jauh pernyataan lisan
yang diberikan oleh seorang Kepala Negara, seorang Menteri Luar Negeri atau menteri-33 A/9610/Rev.1. A/10010/Rev.1 dan A/32/10.34 Report of the International Law Commission on its 17 th and 18 th Sessions (1966), A/6305/Rev.1, hlm.2235 Mc.Nair, Sir Arnold, The Law of Treaties, Oxford 1973, )p.cit.p.736 PCIJ Series A/B No.53 hlm.57.
17
menteri lainnya dalam pemerintahan yang menimbulkan suatu komitmen yang mengikat pada
negara yang bersangkutan. Dalam kasus uji coba nuklir (Australia Vs Perancis ) dalam tahun
1974, Mahkamah telah menghubungkan bobot khusus dari pernyataan-pernyataan yang
dibuat oleh Presiden Perancis, Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri sesudah
dilakukan secara lisan dalam masalah itu. Pernyataan-pernyataan tersebut menurut
Mahkamah kehendak dari Perancis untuk menghentikan uji coba nuklir di udara setelah
selesai serangakaian uji coba yang dilakukan dalam tahun 1974. Dalam memberikan analisa
mengenai arti hukum dari pernyataan-pernyataan tersebut Mahkamah menyatakan sebagai
berikut :
“Mengenai masalah bentuk, harus dilihat bahwa ini bukan dalam wewenang hukum Internasional yang harus menentukan syarat-syarat yang tepat atau khusus. Apakah suatu pernyataan dibuat secara lisan atau tertulis tidak ada perbedaan yang mendasar, untuk penyatuan semacam itu yang dibuat dalam situasi tertentu dapat menimbulkan komitmen dalam Hukum Internasional yang tidak perlu bahwa semua itu harus dilakukan dalam bentuk tertulis”37
Meskipun demikian perlu juga kita meninjau definisi perjanjian internasional
antara negara dan organisasi internasional serta antara organisasi internasional dan
organisasi internasional, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) butir a dari
Konvensi Wina tahun 1986 sebagai berikut :
“Treaty means an international agreement governed by International Law and concluded in written form:
i. Between one or more states and one or more international organisations, or
ii. Between international organisations, wether that agreement is iii. embodied in a single instrument or in two or more related instruments
and whatever its particular designation.
(Perjanjian berarti suatu persetujuan internasional yang diatur oleh hukum Internasional dan dirumuskan dalam bentuk tertulis:
1. antara satu atau lebih negara dan satu atau lebih organisasi internasional; atau
2. sesama organisasi internasional, baik persetujuan itu berupa satu instrumen atau lebih dari satu instrumen yang saling berkaitan dan tanpa memandang apapun juga namanya.)
37 ICJ Report (1974) hlm.267.
18
Menurut I Wayan Parthiana, ke dua macam pengertian perjanjian internasional baik
dalam Konvensi Wina Tahun 1969 maupun dalam Konvensi Wina Tahun 1986 mengandung
unsur atau kualifikasi yang sama seperti kualifikasi perjanjian internasional . Hanya saja
sesuai dengan masing-masing namanya, ruang lingkupnya menjadi lebih sempit. Dapat
dikatakan bahwa ke dua pengertian perjanjian internasional itu merupakan pemisahan dari
pengertian perjanjian internasional berdasarkan pada subyek-subyek hukum yang dapat
membuat ataupun dapat terikat pada suatu perjanjian.38
3. Definition of key terms used in the UN Treaty Collection
Introduction
This introductory note seeks to provide a basic - but not an exhaustive - overview of the key
terms employed in the United Nations Treaty Collection to refer to international instruments
binding at international law: treaties, agreements, conventions, charters, protocols,
declarations, memoranda of understanding, modus vivendi and exchange of notes. The
purpose is to facilitate a general understanding of their scope and function.
Over the past centuries, state practice has developed a variety of terms to refer to
international instruments by which states establish rights and obligations among themselves.
The terms most commonly used are the subject of this overview. However, a fair number of
additional terms have been employed, such as "statutes", "covenants", "accords" and others.
In spite of this diversity of terminology, no precise nomenclature exists. In fact, the meaning
of the terms used is variable, changing from State to State, from region to region and
instrument to instrument. Some of the terms can easily be interchanged: an instrument that is
designated "agreement" might also be called "treaty".
The title assigned to such international instruments thus has normally no overriding legal
effects. The title may follow habitual uses or may relate to the particular character or
importance sought to be attributed to the instrument by its parties. The degree of formality
chosen will depend upon the gravity of the problems dealt with and upon the political
implications and intent of the parties.
38 I Wayan Parthiana, Perjanjian Internasional Bagian I (Bandung: mandar Maju, 2002),hlm.15.
19
Although these instruments differ from each other by title, they all have common features and
international law has applied basically the same rules to all of these instruments. These rules
are the result of long practice among the States, which have accepted them as binding norms
in their mutual relations. Therefore, they are regarded as international customary law. Since
there was a general desire to codify these customary rules, two international conventions
were negotiated. The 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties ("1969 Vienna
Convention"), which entered into force on 27 January 1980, contains rules for treaties
concluded between States. The 1986 Vienna Convention on the Law of Treaties between
States and International Organizations or between International Organizations ("1986 Vienna
Convention"), which has still not entered into force, added rules for treaties with international
organizations as parties. Both the 1969 Vienna Convention and the 1986 Vienna Convention
do not distinguish between the different designations of these instruments. Instead, their rules
apply to all of those instruments as long as they meet certain common requirements.
Article 102 of the Charter of the United Nations provides that "every treaty and every
international agreement entered into by any Member State of the United Nations after the
present Charter comes into force shall as soon as possible be registered with the Secretariat
and published by it". All treaties and international agreements registered or filed and recorded
with the Secretariat since 1946 are published in the UNTS. By the terms "treaty" and
"international agreement", referred to in Article 102 of the Charter, the broadest range of
instruments is covered. Although the General Assembly of the UN has never laid down a
precise definition for both terms and never clarified their mutual relationship, Art.1 of the
General Assembly Regulations to Give Effect to Article 102 of the Charter of the United
Nations provides that the obligation to register applies to every treaty or international
agreement "whatever its form and descriptive name". In the practice of the Secretariat under
Article 102 of the UN Charter, the expressions "treaty" and "international agreement"
embrace a wide variety of instruments, including unilateral commitments, such as
declarations by new Member States of the UN accepting the obligations of the UN Charter,
declarations of acceptance of the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice
under Art.36 (2) of its Statute and certain unilateral declarations that create binding
obligations between the declaring nation and other nations. The particular designation of an
international instrument is thus not decisive for the obligation incumbent on the Member
States to register it.
20
It must however not be concluded that the labelling of treaties is haphazard or capricious. The
very name may be suggestive of the objective aimed at, or of the accepted limitations of
action of the parties to the arrangement. Although the actual intent of the parties can often be
derived from the clauses of the treaty itself or from its preamble, the designated term might
give a general indication of such intent. A particular treaty term might indicate that the
desired objective of the treaty is a higher degree of cooperation than ordinarily aimed for in
such instruments. Other terms might indicate that the parties sought to regulate only technical
matters. Finally, treaty terminology might be indicative of the relationship of the treaty with a
previously or subsequently concluded agreement.
(b) Treaty as a specific term: There are no consistent rules when state practice employs the
terms "treaty" as a title for an international instrument. Usually the term "treaty" is reserved
for matters of some gravity that require more solemn agreements. Their signatures are usually
sealed and they normally require ratification. Typical examples of international instruments
designated as "treaties" are Peace Treaties, Border Treaties, Delimitation Treaties, Extradition
Treaties and Treaties of Friendship, Commerce and Cooperation. The use of the term "treaty"
for international instruments has considerably declined in the last decades in favor of other
terms.
Agreements
The term "agreement" can have a generic and a specific meaning. It also has acquired a
special meaning in the law of regional economic integration.
(a) Agreement as a generic term: The 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties
employs the term "international agreement" in its broadest sense. On the one hand, it defines
treaties as "international agreements" with certain characteristics. On the other hand, it
employs the term "international agreements" for instruments, which do not meet its definition
of "treaty". Its Art.3 refers also to "international agreements not in written form". Although
such oral agreements may be rare, they can have the same binding force as treaties,
depending on the intention of the parties. An example of an oral agreement might be a
promise made by the Minister of Foreign Affairs of one State to his counterpart of another
State. The term "international agreement" in its generic sense consequently embraces the
widest range of international instruments.
21
(b) Agreement as a particular term: "Agreements" are usually less formal and deal with a
narrower range of subject-matter than "treaties". There is a general tendency to apply the term
"agreement" to bilateral or restricted multilateral treaties. It is employed especially for
instruments of a technical or administrative character, which are signed by the representatives
of government departments, but are not subject to ratification. Typical agreements deal with
matters of economic, cultural, scientific and technical cooperation. Agreements also
frequently deal with financial matters, such as avoidance of double taxation, investment
guarantees or financial assistance. The UN and other international organizations regularly
conclude agreements with the host country to an international conference or to a session of a
representative organ of the Organization. Especially in international economic law, the term
"agreement" is also used as a title for broad multilateral agreements (e.g. the commodity
agreements). The use of the term "agreement" slowly developed in the first decades of this
century. Nowadays by far the majority of international instruments are designated as
agreements.
(c) Agreements in regional integration schemes: Regional integration schemes are based on
general framework treaties with constitutional character. International instruments which
amend this framework at a later stage (e.g. accessions, revisions) are also designated as
"treaties". Instruments that are concluded within the framework of the constitutional treaty or
by the organs of the regional organization are usually referred to as "agreements", in order to
distinguish them from the constitutional treaty. For example, whereas the Treaty of Rome of
1957 serves as a quasi-constitution of the European Community, treaties concluded by the EC
with other nations are usually designated as agreements. Also, the Latin American Integration
Association (LAIA) was established by the Treaty of Montevideo of 1980, but the
subregional instruments entered into under its framework are called agreements.
Charters
The term "charter" is used for particularly formal and solemn instruments, such as the
constituent treaty of an international organization. The term itself has an emotive content that
goes back to the Magna Carta of 1215. Well-known recent examples are the Charter of the
United Nations of 1945 and the Charter of the Organization of American States of 1952.
Conventions
The term "convention" again can have both a generic and a specific meaning.
22
(a) Convention as a generic term: Art.38 (1) (a) of the Statute of the International Court of
Justice refers to "international conventions, whether general or particular" as a source of law,
apart from international customary rules and general principles of international law and - as a
secondary source - judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists.
This generic use of the term "convention" embraces all international agreements, in the same
way as does the generic term "treaty". Black letter law is also regularly referred to as
"conventional law", in order to distinguish it from the other sources of international law, such
as customary law or the general principles of international law. The generic term
"convention" thus is synonymous with the generic term "treaty".
(b) Convention as a specific term: Whereas in the last century the term "convention" was
regularly employed for bilateral agreements, it now is generally used for formal multilateral
treaties with a broad number of parties. Conventions are normally open for participation by
the international community as a whole, or by a large number of states. Usually the
instruments negotiated under the auspices of an international organization are entitled
conventions (e.g. Convention on Biological Diversity of 1992, United Nations Convention on
the Law of the Sea of 1982, Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969). The same
holds true for instruments adopted by an organ of an international organization (e.g. the 1951
ILO Convention concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of
Equal Value, adopted by the International Labour Conference or the 1989 Convention on the
Rights of the Child, adopted by the General Assembly of the UN).
Declarations
The term "declaration" is used for various international instruments. However, declarations
are not always legally binding. The term is often deliberately chosen to indicate that the
parties do not intend to create binding obligations but merely want to declare certain
aspirations. An example is the 1992 Rio Declaration. Declarations can however also be
treaties in the generic sense intended to be binding at international law. It is therefore
necessary to establish in each individual case whether the parties intended to create binding
obligations. Ascertaining the intention of the parties can often be a difficult task. Some
instruments entitled "declarations" were not originally intended to have binding force, but
their provisions may have reflected customary international law or may have gained binding
character as customary law at a later stage. Such was the case with the 1948 Universal
23
Declaration of Human Rights. Declarations that are intended to have binding effects could be
classified as follows:
(a) A declaration can be a treaty in the proper sense. A significant example is the Joint
Declaration between the United Kingdom and China on the Question of Hong Kong of 1984.
(b) An interpretative declaration is an instrument that is annexed to a treaty with the goal of
interpreting or explaining the provisions of the latter.
(c) A declaration can also be an informal agreement with respect to a matter of minor
importance.
(d) A series of unilateral declarations can constitute binding agreements. A typical example
are declarations under the Optional Clause of the Statute of the International Court of Justice
that create legal bonds between the declarants, although not directly addressed to each other.
Another example is the unilateral Declaration on the Suez Canal and the arrangements for its
operation issued by Egypt in 1957 which was considered to be an engagement of an
international character.
Exchange of Notes
An "exchange of notes" is a record of a routine agreement, that has many similarities with the
private law contract. The agreement consists of the exchange of two documents, each of the
parties being in the possession of the one signed by the representative of the other. Under the
usual procedure, the accepting State repeats the text of the offering State to record its assent.
The signatories of the letters may be government Ministers, diplomats or departmental heads.
The technique of exchange of notes is frequently resorted to, either because of its speedy
procedure, or, sometimes, to avoid the process of legislative approval.
Memorandum of Understanding
A memorandum of understanding is an international instrument of a less formal kind. It often
sets out operational arrangements under a framework international agreement. It is also used
for the regulation of technical or detailed matters. It is typically in the form of a single
24
instrument and does not require ratification. They are entered into either by States or
International Organizations. The United Nations usually concludes memoranda of
understanding with Member States in order to organize its peacekeeping operations or to
arrange UN Conferences. The United Nations also concludes memoranda of understanding
on cooperation with other international organizations.
Modus Vivendi
A modus vivendi is an instrument recording an international agreement of temporary or
provisional nature intended to be replaced by an arrangement of a more permanent and
detailed character. It is usually made in an informal way, and never requires ratification.
Protocols
The term "protocol" is used for agreements less formal than those entitled "treaty" or
"convention". The term could be used to cover the following kinds of instruments:
(a) A Protocol of Signature is an instrument subsidiary to a treaty, and drawn up by the same
parties. Such a Protocol deals with ancillary matters such as the interpretation of particular
clauses of the treaty, those formal clauses not inserted in the treaty, or the regulation of
technical matters. Ratification of the treaty will normally ipso facto involve ratification of
such a Protocol.
(b) An Optional Protocol to a Treaty is an instrument that establishes additional rights and
obligations to a treaty. It is usually adopted on the same day, but is of independent character
and subject to independent ratification. Such protocols enable certain parties of the treaty to
establish among themselves a framework of obligations which reach further than the general
treaty and to which not all parties of the general treaty consent, creating a "two-tier system".
The Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights of 1966 is a
well-known example.
(c) A Protocol based on a Framework Treaty is an instrument with specific substantive
obligations that implements the general objectives of a previous framework or umbrella
convention. Such protocols ensure a more simplified and accelerated treaty-making process
and have been used particularly in the field of international environmental law. An example
is the 1987 Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer adopted on the
basis of Arts.2 and 8 of the 1985 Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer.
25
(d) A Protocol to amend is an instrument that contains provisions that amend one or various
former treaties, such as the Protocol of 1946 amending the Agreements, Conventions and
Protocols on Narcotic Drugs.
(e) A Protocol as a supplementary treaty is an instrument which contains supplementary
provisions to a previous treaty, e.g. the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees to the
1951 Convention relating to the Status of Refugees.
(f) A Proces-Verbal is an instrument that contains a record of certain understandings arrived
at by the contracting parties.
Signatories and Parties
The term “Parties", which appears in the header of each treaty, in the publication Multilateral
Treaties Deposited with the Secretary-General, includes both "Contracting States" and
"Parties". For general reference, the term "Contracting States" refers to States and other
entities with treaty-making capacity which have expressed their consent to be bound by a
treaty where the treaty has not yet entered into force or where it has not entered into force for
such States and entities; the term "Parties" refers to States and other entities with treaty-
making capacity which have expressed their consent to be bound by a treaty and where the
treaty is in force for such States and entities.)
Treaties
The term "treaty" can be used as a common generic term or as a particular term which
indicates an instrument with certain characteristics.
(a) Treaty as a generic term: The term "treaty" has regularly been used as a generic term
embracing all instruments binding at international law concluded between international
entities, regardless of their formal designation. Both the 1969 Vienna Convention and the
1986 Vienna Convention confirm this generic use of the term "treaty". The 1969 Vienna
Convention defines a treaty as "an international agreement concluded between States in
written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or
in two or more related instruments and whatever its particular designation". The 1986 Vienna
Convention extends the definition of treaties to include international agreements involving
international organizations as parties. In order to speak of a "treaty" in the generic sense, an
instrument has to meet various criteria. First of all, it has to be a binding instrument, which
26
means that the contracting parties intended to create legal rights and duties. Secondly, the
instrument must be concluded by states or international organizations with treaty-making
power. Thirdly, it has to be governed by international law. Finally the engagement has to be
in writing. Even before the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, the word
"treaty" in its generic sense had been generally reserved for engagements concluded in
written form.( Home | Overview | Databases | Publications | Training | Treaty Events | Contacts
UN Homepage | Office of Legal Affairs | UN Publications | Privacy Notice | Disclaimer | Terms of Use
© United Nations, 2013. All Rights Reserved).
4. Hubungan Perjanjian dengan Persetujuan
Mengenai masalah “persetujuan”, pertama, adanya syarat bahwa persetujuan itu harus
diatur oleh hukum Internasional dan harus juga diadakan dalam lingkup Hukum
Internasional, dan haruslah dimaksudkan untuk menghasilkan dampak hukum (Selon les
regles de droit international). Untuk membantu membedakan suatu perjanjian dengan
persetujuan lainnya yang meskipun dibuat antara negara atau subyek hukum internasional
lainnya, diatur bukan oleh hukum Internasional, tetapi oleh hukum nasional dari salah satu
pihak (atau oleh beberapa dari sistem hukum nasional lainnya yang dipilih oleh para pihak).
Suatu contoh seperti kontrak dari negara yang dibuat antara Pemerintah Ruritania dan
Pemerintah Utopia, di mana pemerintah Utopia telah menyetujui untuk menjual kepada
Pemerintah Ruritania sebanyak 1000 ton daging yang didasarkan pada bentuk kontrak yang
sudah baku yang digunakan dalam perdagangan daging. Kontrak semacam itu bukanlah
merupakan sebuah perjanjian dan tidak diatur oleh hukum Internasional tetapi menurut
syarat-syarat kontrak itu sendiri dilengkapi jika perlu dengan prinsip-prinsip hukum secara
umum39. Transaksi-transaksi lainnya dari hukum yang sifatnya privat, seperti sewa rumah dan
gedung dan persetujuan pinjaman, dapat juga berlangsung antara negara, dalam hal seperti itu
akan menjadi sukar untuk menentukan apakah para pihak menghendaki transaksi itu diatur
oleh Hukum Internasional atau oleh prinsip-prinsip hukum umum atau dengan sistem tertentu
dari hukum nasional.40Masalah yang lain nampak pada penggunaan beberapa istilah seperti
yang sudah dibahas pada nomor 3 di atas.
Sudah lama sekali perjanjian telah digunakan oleh banyak negara dengan tujuan untuk
mengusahakan kewajiban yang mengikat di bawah Hukum Internasional satu terhadap yang
39 Mc.Nair, op.cit.hlm.1-540 Lihat Mann, Studies in International Law (1973), hlm.140-225.
27
lain. Dengan demikian berarti negara-negara telah menyetujui untuk membatasi kebebasan
mereka untuk bertindak dalam bidang-bidang tertentu dan untuk mengiukti tindakan-tindakan
tertentu untuk keuntungan bersama. Hyde mengamati bahwa persetujuan antara negara itu
telah dianggap sebagai suatu peristiwa yang diperlukan oleh pergaulan internasional dan
persetujuan tersebut telah meningkat baik jumlah maupun ragamnya karena pergaulan terus
berkembang dan menghasilkan satu kesadaran dan saling ketergantungan. Dalam lingkup dan
polanya, perjanjian-perjanjian itu telah mencatat dengan cermat kebutuhan yang selalu
berubah dalam masyarakat internasional yang tercermin dalam tingkat kemajuan dari negara-
negara tertentu dari keterpencilan menjadi kebersamaan dalam persekutuan dengan negara
lainnya.41
Tidak setiap instrumen internasional, bagaimanapun dikatakan resmi itu akan
dianggap sebagai suatu perjanjian. Kecuali jika instrumen itu menimbulkan kewajiban yang
bersifat kontraktual antara dua negara atau lebih, yang menjadi syarat pokok bagi perjanjian
tidak terpenuhi. Karena itu naskah yang dinyatakan secara sungguh-sungguh atau
ditandatangani oleh wakil-wakil negara atau secara sepihak diumumkan oleh mereka
dapat dianggap dalam keadaan ini sebagai deklarasi mengenai kebijakan (Declaration
of policy), yang walaupun mengikat secara moral dan politik tidak menimbulkan kewajiban-
kewajiban hukum diantara negara-negara. Untuk golongan ini dapat dilihat pada Piagam
Atlantik, yang bersejarah yang dikeluarkan pada tanggal 14 Agustus 1941 yang memasukkan
pernyataan bersama Presiden Roosevelt dan Perdana Menteri Churchill, Deklarasi moskow
tanggal 30 Oktober 1943 mengenai Keamanan secara Umum dan Universal Declaration of
Human Rights .
Sesuai dengan Pasal 2 Konvensi Wina 1969 suatu perjanjian dapat
didefinisikan sebagai suatu persetujuan di mana dua negara atau lebih mengadakan atau
berusaha untuk mengadakan hubungan diantara mereka dan diatur oleh Hukum Internasional.
Selama satu persetujuan antara negara terbukti kebenarannya, dengan pengertian bahwa itu
bukan persetujuan yang diatur oleh hukum nasional domestik, dan asal saja ditujukan untuk
menciptakan suatu hubungan hukum, jenis instrumen atau naskah apapun, atau pertukaran
secara lisan yang diatur oleh negara yang melibatkan perbuatan dapat merupakan perjanjian,
tanpa melihat bentuk atau suasana pembuatannya. Tentu saja istilah “Perjanjian” bisa
dianggap sebagai nomen generalissimum dalam Hukum Internasional, dan dapat
41 Hyde, International Law Chiefly as interpreted and applied in the United Sates, Second Edition, Rev.Ed.Vol II, hlm 1369.
28
memasukkan suatu persetujuan diantara organisasi internasional inter se , atau diantara satu
organisasi internasional di satu pihak dan negara atau negara-negara di pihak lain42. Meskipun
harus diingat bahwa ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina 1969 tidak menerapkan pada
instrumen-instrumen lainnya, tetapi dibatasi pada perjanjian antara negara yang dibuat dalam
bentuk tertulis.43
5. Lebih jauh tentang....TERMINOLOGI DAN PENGKLASIFIKASIAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
42 Cf, the Work of the International law Commission (1980), hlm.88-9143 Lihat Pasal 3 Konvensi Wina 1969.
29
(diambil dari bahan kuliah Hk.Perjanjian Internasional Fakultas Hukum UGM)
Praktek pembuatan perjanjian diantara negara-negara selama ini telah melahirkan berbagai
bentuk terminologi perjanjian internasional yang kadang kala berbeda pemakaiannya menurut
negara, wilayah maupun jenis perangkat internasionalnya. Terminologi yang digunakan atas
perangkat internasional tersebut umumnya tidak mengurangi hak dan kewajiban yang
terkandung di dalamnya. Hal ini berbeda dengan ketentuan perundangan dalam Hukum
nasional Indonesia yang mengenal adanya hierarkhi peraturan perundang-undangan, dalam
perjanjian internasional berbagai penamaan perjanjian internasional mempunyai konsekuemsi
hukum yang sama.
Konvensi Wina tahun 1969 mengenai Hukum Perjanjian Internasional dan Konvensi
Wina Tahun 1986 mengenai Hukum Perjanjia Internasional antara Negara dan Organisasi
Internasional atau antar Organisasi-Organisasi Internasional tidak melakukan pembedaan atas
berbagai bentuk Perjanjian Internasional. Selain itu Pasal 102 Piagam PBB hanya
membedakan Perjanjian Internasional menurut terminologi “Treaty” dan “International
Agreement”, yang hingga saat inipun tidak ada definisi yang tegas antara ke dua terminologi
tersebut. Beberapa penamaan dari Perjanjian Internasional yang ada antara lain:
Treaties (Traktat) Convention ( Konvensi) Letter of Intent Agreement (Persetujuan) Charter (Piagam) Protocol (Protokol) Declaration (Deklarasi) Final Act Summary Records Memorandum of Understanding Arrangement Exchange of Notes Modus Vivendi Side Letter Joint Statement Joint Declaration Memorandum of Cooperation Letter of Agreement Letter of Understanding Record of Understanding Minutes of Meeting Agreed Minutes
30
Meskipun secara hukum beragam penamaan ini mempunyai konsekuensi yang sama,
akan tetapi untuk kebutuhan praktis umumnya penamaan “Perjanjian Internasional” akan
mengarah pada kesamaan materi perjanjian dan juga sebagai indikator bobot kerjasama yang
diatur dalam perjanjian atau untuk menunjukkan hubungan antara satu perjanjian
internasional dengan perjanjian internasional lainnya.
Selain dikenal adanya berbagai penamaan perjanjian internasional, untuk tujuan
pemahaman tentang perjanjian internasional, juga dibuat beberapa pengklasifikasian
perjanjian internasional menurut cara peninjauan terhadap perjanjian internasional. Ada
beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam pengklasifikasian perjanjian internasional.
Beberapa kriteria tersebut antara lain :
1. Berdasarkan Petugas yang membuat perjanjian Internasional
a. Perjanjian Internasional antar kepala Negara;b. Perjanjian Internasional antar Kepala Pemerintah;c. Perjanjian Internasional antar Menteri.
Perbedaan perutusan tersebut tidak mempengaruhi kekuatan mengikatnya Perjanjian
Internasional. Pernyataan menteri Luar negeri suatu negara kepada Menteri Luar negeri
negara lain sama kekuatan mengikatnya dengan Perjanjian antar Kepala Negara. Bagi
Hukum Internasional isi dan substansi perjanjian internasional lebih penting dari pada
siapa delegasi dalam perundingan.
2. Berdasarkan Proses Pembentukannya.
a. Perjanjian Internasional yang diadakan melalui tiga tahap, yaitu Perundingan,
Penandatanganan dan Ratifikasi (Pengesahan). Biasanya perjanjian semacam ini
diadakan untuk hal-hal yang dianggap sangat penting/vital, sehingga memerlukan
persetujuan badan-badan yang berwenang untuk mengadakan perjanjian.
b. Perjanjian Internasional yang diadakan hanya melalui dua tahap, yaitu Perundingan
dan Penandatanganan, tanpa Ratifikasi. Biasanya merupakan perjanjian-perjanjian
yang tidak begitu penting/vital, sederhana dan memerlukan penyelesaian yang
cepat/segera. Misalnya Perjanjian Perdagangan Jangka Pendek, dan sebagainya.
c. Berdasarkan Jumlah Peserta Dalam Perundingan.
1) Traktat Bilateral , yaitu traktat/perjanjian internasional yang diadakan oleh dan
antara dua pihak;
31
2) Traktat Multilateral yaitu Traktat/Perjanjian Internasional yang diadakan
banyak pihak/lebih dari dua pihak.
d. Berdasarkan Hakikatnya (langsung dan Tidak Langsung Membentuk Hukum)
1) Treaty Contract , yaitu traktat-traktat yang tidak langsung membentuk hukum dan
hanya membentuk hukum secara tidak langsung melalui Hukum Kebiasaan.
Traktat ini umumnya hanya menimbulkan akibat-akibat hukum bagi para pihak
yang mengadakan perjanjian saja. Umunya Treaty Contract bersifat Perjanjian
Bilateral, dimana pihak ke tiga tidak dapat turut serta dalam Treaty Contract, yang
diadakan oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian semula. Misalnya :
“Arrangement between the Government of the Republic of Indonesia and the
Government of the Republic of Iran on Cultural Exchange Programme Years
2006-2008.
2) Law Making Treaty , yaitu traktat-traktat yang langsung membentuk hukum atau
perjanjian-perjanjian internasional yang meletakkan ketentuan-ketentuan/kaidah-
kaidah hukum masyarakat Internasional secara keseluruhan. Umumnya “law
Making Treaty” bersifat Perjanjian Multilateral dan terbuka untuk pihak-pihak di
luar peserta perundingan untuk menyatakan keikutsertaannya dalam perjanjian
tersebut. Misalnya : “Asean Framework Agreement on Mutual Recognition
Arrangements 1998”
BAB III
BEBERAPA ASPEK DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL.
A.Proses Pembuatan Perjanjian Internasional.
Proses pembuatan Perjanjian Internasional bukanlah proses yang sederhana apalagi
jika masalah yang dibahas merupakan isu-isu yang penting. Umumnya diperlukan waktu
32
yang cukup lama untuk menghasilkan suatu perjanjian internasional. Misalnya untuk
melahirkan Konvensi PBB tentang Hukum laut III (United Nations Conference on the Law of
the Sea /UNCLOS III) diperlukan waktu selama 9 tahun.44 Hal ini karena proses pembuatan
Perjanjian Internasional merupakan rangkaian dari tahap-tahap penting sebagai berikut:
PI Berlaku
Perundingan/Negosiasi Persetujuan Saat Mulai Berlakunya PI
Verifikasi delegasi Penandatanganan Pendaftaran PI ke Lembaga
Penyimpanan dan UNTS
Penunjukan delegasi Naskah PI Exists Ratifikasi/aksesi
(multilateral)
Negara/org.Int. Tukar menukar Instrumen
Penandatanganan (Bilateral) Pendaftaran PI ke UNTS
1. Penunjukan Delegasi dan verifikasi Delegasi.
Untuk membuat perjanjian internasonal baik negara maupun organisasi internasional
memerlukan petugas untuk melakukan perundingan. Dalam Pasal 7 Konvensi Wina 1969
disebutkan bahwa para pihak yang secara otomatis dapat mewakili suatu negara tanpa melalui
harus memiliki full power adalah :
a. Kepala Negara, Kepala Pemerintahan dan Menteri Luar Negeri untuk maksud
melakukan semua tindakan yang berhubungan dengan penutupan suatu perjanjian;
b. Kepala Misi diplomatik untuk maksud menyetujui teks perjanjian antar negara
pengirim dan negara dimana mereka diakreditasikan;
44 Proses pembuatan UNCLOS III dimulai dari desember 1973 sampai September 1982 yang secara keseluruhan berjumlah i2 kali sidang. Konvensi ini diterima dalam Konferensi Hukum Laut III pada tanggal 30 April 1982 di New York untuk ditandatangani mulai tanggal 10 desember 1982 di montego bay Jamaika.
33
c. Wakil-wakil yang dikirim oleh suatu negara kepada suatu Konferensi internasional
atau organisasi internasionl atau satu dari organ-organnya untuk maksud menyetujui
teks perjanjian di dlam konferensi itu, organisasi itu atau organ-organnya.
Selain pihak-pihak yang disebutkan di atas, maka seorang delegasi untuk menjadi
wakil dalam suatu perundingan harus memiliki dokumen yang disebut “Full Power”, yakni
suatu dokumen yang berasal dari penguasa yang berwenang dari suatu negara yang menunjuk
seseorang atau orang-orang untuk mewakili negara tersebut untuk berunding, menyetujui atau
mengesahkan teks suatu perjanjian, untuk menyatakan persetujuan negara terikat pada
perjanjian atau untuk menyelesaikan tindakan-tindakan lainnya yang berkenaan dengan suatu
perjanjian. Full power ini umumnya berisi nama-nama utusan dan juga luasan wewenang
yang dimiliki. Dalam Perjanjian Internasional multilateral pemberitahuan itu dilakukan
melalui panitia yang kemudian melaporkannya kepada Konferensi.
Disamping Full Power suatu delegasi yang menghadiri suatu konferensi internasional
dalam kerangka suatu organisasi internasional biasanya dilengkapi dengan “Credential” atau
surat kepercayaan. Menurut Pasal 27 Rules of Procedure of the General Assembly, surat-
surat kepercayaan delegasi suatu negara k Majelis Sidang Umum PBB harus diserahkan ke
Sekretaris Jenderal seminggu sebelum sidang dimulai. Jadi yang diperlukan untuk PBB dan
Badan-Badan Subsider lainnya adalah surat-surat kepercayaan dan bukan Full Power. Bagi
PBB surat kepercayaan ini adalah mutlak-untuk mengetahui dan kalau perlu memutuskan
delegasi mana yang betul-betul mewakili suatu negara bila terdapat Pemerintah tandingan
dari suatu negara.
2.Perundingan/Negosiasi dan Persetujuan.
Perundingan dalam pembuatan Perjanjian Internasional bilateral dilakukan dengan
saling bicara secara langsung, sementara dalam pembuatan perjanjian internasional
multilateral perundingan dilakukan dalam konferensi diplomatik. Konferensi diplomatik itu
merupakan perundingan yang resmi. Disamping perundingan resmi itu dapat pula dilakukan
perundingan yang tidak resmi di luar konferensi. Dalam tahapan ini para delegasi tetap
mengadakan hubungan dengan Pemerintah masing-masing untuk berkonsultasi cara untuk
mempertahankan konsep dari pemerintahnya dan untuk mendapatkan instruksi-instruksi baru
34
terkait dengan masalah yang dibahas. Perundingan diharapkan ditutup dengan penetapan
keputusan yang diperjanjikan. Penetapan keputusan itu, dalam Perjanjian Internasional
Bilateral dilakukan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang berjanji, sementara
dalam Perjanjian Internasional Multilateral, penerimaan naskah dapat ditentukan dengan :
-Unanimity System (Sistem Kebulatan Suara). Menurut sistem ini, suatu hal untuk dapat
disetujui atau dicapai kata sepakat akan berlaku mengikat jika mendapat persetujuan dari
seluruh negara peserta pada Perjanjian Internasional tersebut atau seluruh negara yang terlibat
dalam proses perundingan untuk memutuskan naskah suatu perjanjian internasional.. Jika
ternyata ada satu negara saja menyatakan ketidaksetujuannya, maka kata sepakat tersebut
tidak dapat tercapai.
-Pan America System. Menurut sistem ini untuk tercapainya sebuah kesepakatan tidak
diperlukan diperlukan adanya persetujuan bulat dari seluruh negara peserta, namun
ditetapkan sesuai dengan besaran yang disepakati bersama di antara para pihak, misalnya
persetujuan teks perjanjian terjadi dengan suara 2/3 negara yang hadir dalam memberikan
suara. Sistem ini disebut dengan Teori Pan Amerika karena untuk pertama kalinya
diperkenalkan dan dianut oleh negara-negara yang ada di Benua Amerika yang tergabung
dalam organisasi Negara-Negara Amerika (Organization of American states/OAS) pada
Tahun 1932. Negara yang berpartisipasi dalam negosiasi disebut “Negara Peserta”
(Contracting States).
3. Penandatanganan.
Apabila draft final Perjanjian Internasional telah disetujui, berarti instrumen ini telah
siap untuk ditandatangani. Dalam praktek, umumnya akan ada jeda waktu yang cukup antara tahap persetujuan dan penandatanganan. Kondisi ini dimaksudkan agar para
delegasi mempunyai waktu yang cukup untuk mempelajari dan berkonsultasi terlebih
dahulu dengan pemerintahnya sebelum mengambil sikap untuk menandatangani atau tidak
draft final yang ada. Tahap penandatanganan biasanya merupakan hal yang paling formal di
mana tindakan penandatanganan merupakan hal yang essensial bagi suatu perjanjian
internasional, karena terutama penandatangananlah yang memberi status otentik suatu teks
perjanjian internasional. Disamping memberikan status otentik dalam Perjanjian Internasional
yang dalam kategori tidak membutuhkan adanya ratifikasi maka penandatanganan ini juga
35
berarti saat mengikatnya perjanjian internasional, jadi perjanjian akan berlaku sejak
penandatanganan.
4.Ratifikasi/Aksesi (Consent to be bound).
Ratifikasi adalah proses yang dilalui oleh pemerintah atau organisasi internasional
untuk secara resmi menyatakan terikat oleh traktat atau perjanjian internasional lain setelah
pemerintah atau organisasi internasional menandatanganinya. Ratifikasi ini merupakan tahap
wajib yang harus dilakukan dalam pembuatan sebuah perjanjian internasional, khususnya
perjanjian internasional yang sifatnya multilateral sebagai tanda penerimaan atau pengesahan
terhadap sebuah naskah perjanjian internasional untuk menciptakan ikatan hukum bagi para
pihaknya.45 Keharusan adanya tahap ratifikasi dalam perjanjian internasional ini karena
hukum internasional mempunyai karakter yang berbeda dengan hukum nasional terkait
dengan masalah pemberlakuannya, jika hukum nasional akan mengikat semua warga negara
dalam satu negara sejak diundangkan, Hukum Internasional tidak dapat secara Ex
propiovigore berlaku secara efektif dalam suatu negara sebelum ada proses transformasi 46maupun delegasi47.
Seiring dengan berkembangnya prinsip-prinsip demokrasi dan prinsip kedaulatan
negara, maka mekanisme ratifikasi ini makin banyak digunakan karena dirasa perlu untuk
memeriksa lagi perjanjian yang telah dibuat dan yang telah ditandatangani para delegasi.
Proses koreksi terhadap perjanjian ini selain dimaksudkan untuk mempelajari kembali isi dari
perjanjian dan melihat pada kondisi dalam negeri apakah sudah siap jika perjanjian tersebut
akan diterapkan, juga dimaksudkan sebagai pelaksanaan hak legislatif dari parlemen untuk
45 Catatan: ada beberapa perjanjian internasional yang dalam proses pembuatannya tidak mewajibkan untuk melakukan ratifikasi namun hanya dengan penandatanganan saja sudah dapat menciptakan ikatan hukum dengan negara pihak. Biasanya perjanjian internasional semacam ini adalah perjanjian internasional yang sifatnya bilateral, atau materi yang diatur hanya materi sederhana, dan itupun harus dinyatakan dalam salah satu pasal dalam klausula formal perjanjian bahwa perjanjian tersebut berlaku sejak diadakan penandatanganan perjanjian oleh para pihak. Sebagian besar perjanjian internasional yang ada mewajibkan adanya tahap ratifikasi, sementara penandatanganan hanya dimaksudkan sebagai persetujuan atau legalitas atas naskah yang dihasilkan menjadi naskah autentik.46 Teori ini mengatakan bahwa untuk berlakunya Hukum Internasional dalam hukum nasional perlu ditransformasikan melalui sebuah adopsi khusus (Sugeng Istanto, 1998, Hukum Internasional, Universitas Atmajaya Yogyakarta, halaman 7)47 Teori ini juga mengatakan bahwa untuk berlakunya Hukum Internasional dalam Hukum Nasional perlu ditransformasikan melalui sebuah adopsi khusus, namun adopsi di sini bukan sebuah proses transformasi namun merupakan kelanjutan satu proses pembentukan hukum yang dimulai dari penetapan perjanjian internasional sampai menjadi ketentuan hukum yang mengikat umum dalam satu negara.
36
turut serta dalam proses pembuatan perjanjian internasional48. Secara detail tujuan dari
ratifikasi adalah sebagai berikut :
a. Pelaksanaan Perjanjian Internasional menyangkut kepentingan dan mengikat masa
depan negara dalam hal-hal tertentu, karena itu harus disahkan oleh kekuasaan negara
tertinggi;
b. Untuk menghindari kontroversi antara utusan-utusan yang berunding dengan
Pemerintah yang mengutus mereka;
c. Perlu adanya waktu agar instansi-instansi yang bersangkutan dapat mempelajari
naskah yang diterima;
d. Pengaruh rezim parlementer yang mempunyai wewenang untuk mengawasi kegiatan-
kegiatan eksekutif;
Dalam Pasal 14 Konvensi Wina 1969 dijelaskan bahwa persetujuan suatu negara
untuk diikat suatu perjanjian dinyatakan dalam bentuk ratifikasi apabila:
a. Perjanjian itu sendiri mengharuskan supaya persetujuan diberikan dalam bentuk
ratifikasi;
b. Bila terbukti bahwa negara-negara yang ikut berunding setuju untuk ratifikasi;
c. Bila utusan-utusan negara menandatangani perjanjian tersebut dengan syarat untuk
meratifikasinya kemudian, atau;
d. Full Powers delegasi itu sendiri menyatakan bahwa ratifikasi diharuskan kemudian.
Ratifikasi merupakan hak sepenuhnya dari negara yang berdaulat yang tidak dapat
dipaksakan oleh negara atau organisasi ingernasional manapun, walaupun negara tersebut
telah membubuhkan persetujuan terhadap materi dalam perjanjian lewat penandatanganan
karena ini terkait dengann kekuatan dan kesiapan sebuah bangsa untuk menerima
konsekuensi atas hak dan kewajiban yang terlahir dari perjanjian tersebut. Konsekuensi dari
pernytaan terikat dalam sebuah perjnjian, maka sebuah negara pihak selain berhak untuk
menikmati semua hak-hak yang disediakan juga wajib untuk memenuhi semua kewajiban
yang terlahir dari perjanjian tersebut. Prinsip ini dikenal dengan “Pacta Sunt Servanda”,
bahwa dalam sebuah perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai undang-undang
48 Catatan: umumnya delegasi yang mewakili suatu negara dalam pembuatan sebuah perjanjian internasional adalah wakil eksekutif.
37
bagi mereka yang membuatnya dan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat
para pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.49
Suatu negara adakalanya menglami kesulitan atau sangat terlambat sekali dan
bahkan tidak melakukan sama sekali untuk menjadi pihak atau meratifikasi konvensi-
konvensi atau perjanjian internasional walaupun instrumen internasional tersebut
penting bagi negara yang bersangkutan. Hal ini terjadi karena dijumpainya kendala-
kendala di dalam proses ratifikasi perjanjian internasional. Menurut Prof.Dr.Sumaryo
Suryokusumo, SH.LLM kendala-kendala tersebut pada hakekatnya disebabkan oleh :
a. Constitutional Factor
Masalah konstitusional merupakan salah satu faktor yang menjadi kendala bagi
peratifikasian perjnjian internasional oleh suatu negara. Hal ini terkait adanya satu
atau beberapa ketentuan dalam konstitusi negara yang bersangkutan yang
berlawanan dengan satu atau beberapa ketentuan yang ada dalam perjanjian
internasional yang akan diratifikasi. Kendala semacam ini dalam banyak kasus di
beberapa negara tidak saja menghambat ratifikasi namun sampai pada sikap negara
untuk tidak meratifikasi perjanjian tersebut atau menunggu sampai dengan ada
amandemen konstitusi negara yang bersngkutan untuk menyesuaikan ketentuan yang
bertentangan dengan perjanjian internasional, baru kemudian dapat untuk diratifikasi.
b. Jurisdictional Factor
Kendala yurisdiksi adalah kendala yang disebabkan karena negara yang
bersangkutan tidak mau mengakui jurisdiksi dari mahkamah Internasional50,
padahal dalam salah satu pasal dari perjanjian internasional tersebut memuat
ketentuan bahwa dalam hal terjadi sengketa yang terkait dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban yang terlahir dari perjanjian tersebut, penyelesaiannya diserahkan kepada
Mahkamah Internasional, dan dalam perjanjian tersebut juga tidak memperbolehkan
adanya reservasi.
c. Substantive Factor
49 Lihat Sudarsono, kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.50 Pada prinsipnya yurisdiksi dari mahkamah Internasional sifatnya non compulsory, wewenang wajib dari mahkamah Internasional hanya dapat terjadi bila negara negara sebelumnya dalam suatu persetujuan menerima wewenang tersebut (Boer Mauna, 2005, Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam era Dinamika Global, PT Alumni Bandung Edisi ke 2, hlm.260.
38
Faktor substansi menghambat proses ratifikasi oleh berbagai negara di dunia. Kendala
ini lebih kepada substansi yang diatur dari perjanjian internasional yang
bersangkutan yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi dalam negara yang
bersangkutan. Umumnya ketidaksesuaian substansi ini bisa dilihat dari aspek politik,
ekonomi, sosial dan budaya serta teknis pelaksanaannya perjanjian internasional
tersebut apabila diterapkan oleh negara yang bersangkutan. Di dalam negara-negara
berkembang dan dalam kategori yang masih terbelakang umumnya faktor substansi
ini juga berkaitan dengan kesulitan dari pihak legislatif untuk memahami materi yang
diatur dalam perjanjian tersebut, sehingga dalam proses pembahasan untuk
peratifikasian perjanjian internasional tersebut mengalami keterlambatan dan
berkepanjangan dan bahkan sampai tertunda. Di beberapa negara selain berbagai
komisi yang dibentuk juga ada komisi ahli (expert Commission) yang anggotanya
para pakar berbagai bidang dan bukan merupakan anggota parlemen (Non
parliamentarian) yang bertugas untuk membahas secara substantif permasalahannya
sehingga dapat memberikan rekomendasi dari parlemen untuk pengesahan terakhir.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh suatu negara sebelum melakukan proses
ratifikasi adalah :
a. Apakah materi yang diatur dalam perjanjian tersebut berkaitan dengan
kepentingan nasional negara tersebut ;
b. Apakah konsekuensi hukum yang terlahir dari perjanjian tersebut sudah
mampu untuk dilaksanakan oleh negara tersebut :
c. Apakah perjanjian internasional yang bersangkutan memungkinkan bagi
negara tersebut untuk melakukan reservasi51 atau deklarasi 52
Sebenarnya penggunaan kata ratifikasi dewasa ini tidaklah seperti istilah
ratifikasi yang dimaksudkan dalam Konvensi Wina tahun 1969, dimana istilah
ratifikasi ini lebih dimaksudkan sebagai pengesahan atas perjanjian internasional.
51 Reservasi adalah pernyataan sepihak bagaimanapun diungkapkan atau dinamakan yang dibuat oleh suatu negara ketika menabndatangani, mengesahkan, menerima, menyetujui atau ikut serta pada suatu perjanjian dengan mana ia mengakui meniadakan atau mengubah akibat hukum dari ketentuan-ketentuan tertentu suatu perjanjian dalam penerapannya terhadap perjanjian tersebut (Sumaryo Suryokusumo, Studi kasus Hukum Internasional, Tata Nusa Jakarta, hlm.179).52 Deklarasi adalah pernyataan sepihak suatu negara tentang pemahaman atau penafsiran mengenai suatu ketentuan dalam perjanjian internasional yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui atau mengesahkan perjanjian internasional yang bersifat multilateral guna memperjelas makna ketentuan tersebut dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi hak dan kewajiban negara dalam Perjanjian Internasional (Pasal 1 poin (6) UURI No.24 tahun 2000 tentang Pwerjanjian Internasional)
39
Menurut Konvensi Wina 1969 Pasal 2 (b) sebenarnya pengesahan suatu perjanjian
internasional tidak harus selalu dengan ratifikasi melainkan dapat dengan :
a. Ratifikasi (Ratification), adalah bentuk pengesahan terhadap perjanjian yang
sudah ditandatangani oleh delegasi dari suatu negara (Negara yang
bersangkutan termasuk sebagai negara perunding/negosiating state);
b. Aksesi (Accession) adalah pengesahan terhadap perjanjian yang tidak
ditandatangani (Negara yang bersangkutan bukan merupakan negara
perunding dalam perjanjian yang disahkan),;
c. Penerimaan (Acceptance) dan Penyetujuan (Approval); acceptance adn
approval adalah pernyataan menerima atau menyetujui dari negara-negara
pihak dalam suatu perjanjian internasional atas perubahan perjanjian
internasional tersebut (Direktorat Jenderal hukum dan Perjanjian Internasional
2006, Pedoman Teknis dan Referensi tentang Pembuatan Perjanjian
Internasional, Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya, Direktorat
jenderal hukum Dan Perjanjian Internasional, Departemen Luar negeri jakarta,
hlm.30).
Adapun mengenai bentuk mana yang harus diambil oleh suatu negara untuk
melakukan pengesahan terhadap perjanjian internasional pada umumnya diatur lebih
rinci oleh perjanjian itu sendiri dengan memperhatikan prinsip umum dalam
perjanjian internasional.
Adapun mengenai mekanisme ratifikasinya, Hukum Internasional memberikan
kewenangan kepada masing masing negara untuk mengatur mekanismenya menurut
konstitusi negara masing-masing. Hal ini karena pengaturan tentang kewenangan
kekuasaan pembuatan perjnjian internasional antara satu negara dengan negara lain
tidak sama. Secara umum ada tiga tipe kewenangan kekuasaan pembuatan perjanjian
internasional.
a. Kewenangan mutlak eksekutif;
Kewenangan ini pada umumnya terdapat pada sistem monokrasi dengan
kekuasaan terkonsentrasi pada Kepala negara sebagai kepala eksekutif. Sistem
ini umumnya dipkai dalam sistem monarkhi absolut;
b. Kewenangan mutlak legislatif’
40
Kewenangan ini umumnya berkembang pada saat di mana lembaga legislatif
suatu kekuasaan termasuk di dalamnya kekuasaan pembuatan perjanjian;
c. Pembagian kewenangan antara eksekutif dan legislatif.
Kewenangan untuk membuat perjanjian berada di tangan lembaga eksekutif,
namun untuk melaksanakan kewenangan tersebut lembaga eksekutif harus
mendapat persetujuan dari lembaga legislatif. Jadi di sini menekankan pada
perlunya kerjasama antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam pembuatan
perjanjian internasional.
5.Pendaftaran dan Publikasi Perjanjian Internasional.
Proses pendaftaran dan publikasi suatu perjanjian internasional merupakan proses
yang penting. Semua perjanjian internasional baik yang sifatnya bilateral maupun multilateral
sesegera mungkin harus didaftarkan pada Sekretariat PBB setelah berlaku sesuai dengan
Pasal 102 piagam PBB, Pendaftaran itu disertai pula dengan publikasinya secara luas dan
terbuka dalam The United Nations Treaty Series (UNTS). Akibat dari pendaftaran dan
pengumuman itu ialah bahwa perjanjian internasional itu dapat digunakan sebagai dasar
hukum di hadapan organ PBB. Tidak didaftarkan perjanjian internasional itu tidak berarti
batalnya perjanjian tersebut. Perjanjian yang tidak didaftarkan masih daoat digunakan sebagai
dasar hukum di hadapan badan atau peradilan di luar PBB.
Disamping pendaftaran ke PBB, untuk Perjanjian Internasional yang sifatnya
multilateral juga diwajibkan untuk didaftarkan pada lembaga penyimpan yang ditunjuk dalam
perjanjian pada saat negara menyatakan ratifikasi atau aksesinya, dengan kewajiban lembaga
penyimpan untuk mencatat dan menginformasikannya kepada seluruh negara pihak. Hal ini
dimaksudkan untuk mengetahui posisi suatu negara dalam suatu perjanjian internasional
beserta hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian internasional tersebut.
6.Saat Mulai Berlakunya Perjanjian (Enter into Force Treaty).
Menurut ketentuan Pasal 24 ayat (1) Konvensi Wina 1969, berlakunya suatu
perjanjian internasional tergantung pada :
a. Ketentuan perjanjian itu sendiri;b. Atau apa yang telh disetujui oleh negara peserta.
41
Dalam praktek suatu perjanjian dapat berlaku pada saat :
a. Penandatanganan Perjanjian;
b. Pada tanggal yang disepakati melalui pertukaran Nota (Exchange of Notes).
c. Penyampaian notifikasi bahwa prosedur internal telah dipenuhi;
d. Pertukaran Piagam Pengesahan;
e. Pengesahan;
f. Cara lain yang disepakati para pihak, misalnya Simlified Procedure, yakni
keterikatan secara otomatis pada Perjanjian Internasional, apabila dalam masa
tertentu tidak menyampaikan notifikasi tertulis untuk menolak keterikatannya
pada suatu perjanjiaj internasional.
B.Bahasa Perjanjian Internasional.
Masalah bahasa dalam pembuatan perjanjian Internasional merupakan satu hal
penting yang perlu mendapat pengaturan secara khusus. Hal ini mengingat para pihak dalam
Perjanjian Internasional, umunya memiliki bahasa nasional yang berbeda-beda sehingga
untuk menghindari penafsiran yang berbeda atas materi perjanjian internasional. Perlu
disepakati aturan tertentu dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian. Beberapa pengaturan
masalah bahasa dalam Perjanjian Internasional adalah sebagai berikut :
1. Perjanjian Internasional Bilateral.
Untuk Perjanjian Internasional yang sifatnya bilateral, pengaturannya tidak begitu
rumit. Naskah perjanjian pada prinsipnya cukup dibuat dalam bahsa nasional masing-
masing pihak berdasarkan urutan abjad dalam Bahasa Inggris dan dalam bahasa
Inggris naskah terakhirnya . Sebagai contoh :
a. Indonesia (bahasa Indonesia)+Mesir (bahasa Arab)= naskahnya dalam Bahsaa
Arab , Indonesia dan Inggris.
b. Indonesia (Bahasa Indonesia+Singapura (Bahasa Inggris); Naskahnya cukup
dalam Bahasa Indonesia dan Inggris;
Demikian juga jika pihaknya tiga atau empat negara, umumnya mekanisme
pengaturan bahasanya seperti dalam pengaturan dalam Perjanjian Internasional
Bilateral. Misalnya jika pihaknya Indonesia, India, Thailand dan Inggris. Dalam
pelaksanaannya nanti, jika terjadi perbedaan dalam hal penafsiran teks perjanjian
42
internasional, maka naskah dalam Bahasa Inggrislah yang diutamakan
penggunaannya.
2. Perjanjian Internasional Multilateral.
Pada perjanjian internasional yang sifatnya multilateral pengaturannya berbeda. Hal
ini karena dalam perjanjian ini umumnya pihaknya sangat banyak bahkan sampai
mencapai ratusan, sehingga sangat menyulitkan jika harus dibuat dalam masing-
masing bahasa dari negara pihak. Dalam praktekny, umumnya negara hanya memilih
Bahasa Inggris saja sebagai bahasa resminya, sementara di PBB ada enam bahasa
resmi yaitu : Inggris, Perancis, Spanyol, China Rusia dan bahasa Arab. Pada
prinsipnya dalam Perjanjian Internasional multilateral bahasa apa saja yang dianggap
resmi tidak ada ketentuannya secara baku, namun tergantung pada keinginan para
negara perunding yang akan dituangkan juga dalam salah satu pasal dalam Perjanjian
Internasional tersebut.53
C. Pensyaratan (Reservation)
Pensyaratan (Reservation) adalah suatu sistem, di mana suatu negara yang
merupakan pihak pada perjanjian dapat menyatakan pensyaratan pada pasal-pasal
tertentu. Jadi, kalau pensyaratan tersebut diterima, maka negara yang bersangkutan
dapat menolak pelaksanaan pasal-pasal tersebut untuknya. Pensyaratan dapat diajukan
waktu penandatanganan, ratifikasi, akseptasi, aprobasi dan aksesi.
Bila pensyaratan ini dimungkinkan, jumlah pihak pada suatu perjanjian
menjadi lebih banyak, namun sistem ini dapat pula menimbulkan kesukaran-
kesukaran karena uniformitas perjanjian menjadi tidak terjaga karena pensyaratan
suatu negara dapat berlainan dengan pensyaratan negara lain. Disamping itu integritas
perjanjian tidak terjamin lagi dan akan sulit juga untuk diketahui pasal-pasal mana yan
berlaku dan tidak berlaku bagi suatu negara.
Walaupun sistem ini menimbulkan kesulitan-kesulitan namun praktek
internasional memberikan kebebasan untuk melakukan pensyaratan. Mahkamah
53 Misalnya dalam article 53 The International Covenant on Civil and Political Rights dinyatakan : “The present Covenant, of which the Chinese, English, french, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited in the archives of the United Nations”.
43
Internasional dalam pendapatnya yang dikeluarkan tanggal 28 mei 1951 mengakui
praktek pensyaratan dengan memberikan pembatasan rangkap:
1. Pensyaratan tidak boleh bertentangan dengan maksud dan tujuan perjanjian:
2. Negara yang menyatakan keberatannya terhadap pensyaratan yang diajukan
oleh negara lain dapat menganggap dirinya tidak terikat dalam perjanjian
dengan negara tersebut.
Bagaimana pendapat Konvensi Wina ? Pasal 19 konvensi Wina menyatakan :
Suatu negara waktu menandatangani, meratifikasi, menerima atau aksesi dapat mengajukan pensyaratan terhadap suatu perjanjian kecuali:
1. Pensyaratan dilarang oleh perjanjian;2. Pensyaratan tertentu di mana tidak termasuk pensyaratan yang
dilarang;3. Pensyaratan tersebut tidak sesuai dengan maksud dan tujuan
perjanjian.
Disamping itu konvensi mengajukan beberapa ketentuan tambahan:
1. Bila suatu negara keberatan terhadap suatu pensyaratan yang diajukan oleh negara lain, karena pensyaratan tersebut bertentangan dengan maksud dan tujuan perjanjian, dan bila negara pertama tadi tidak keberatan agar perjanjian tersebut berlaku juga dalam hubungannya dengan negara ke dua, tentu yang tidak berlaku itu hanyalah pensyaratan itu saja.
2. Suatu pensyaratan yang secara tegas diijinkan oleh suatu perjanjian, tentu tetap berlaku bagi negara-negara lain;
3. Kalau perjanjian multilateral tersebut hanya diikuti oleh sejumlah kecil negara dan persetujuan semua negara dibutuhkan untuk menjaga keutuhan ketentuan perjanjian tadi, tentu saja suatu pensyaratan perlu persetujuan semua negara peserta.
Dalam prakteknya, pensyaratan yang dilakukan Indonesia dalam perjanjian-
perjanjian multilateral sampai sekarang sering menyangkut persoalan penyelesaian
sengketa, misalnya pensyaratan terhadap Pasal 24 ayat 1 pada Convention on
Offences and certain Other Acts Committed on Board Aircraft (Tokyo, 14 Septem,ber
1963), Pasal 12 ayat 1 pada Convention for Suppression of Unlawful Seizure of
Aircraft (Den Haag, 16 desember 1970) dan Pasal 14 ayat 1 pada Convention for the
Suppression on Unlawful Acts Against the safety of Civil Aviation (Montreal, 23
September 1971), di mana dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa ke Mahkamah
Internasional harus sebelumnya mendapat persetujuan pihak-pihak yang bersengketa.
44
D. Unsur-Unsur Formal Naskah Suatu Perjanjian.
Biasanya unsur-unsur formal suatu perjanjian terdiri dari-Mukadimah,
Batang-Tubuh, Kalusula-Klausula Penutup dan Annex.
1.Mukadimah.
Biasanya mukadimah suatu perjanjian mulai dengan menyebutkan negara-
negara peserta. Perjanjian yang dibuat dalam Kerangka ASEAN pada umumnya mulai
dengan: The Government of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the
Republic of Indonesia, the Lao People’s Democratic Republic, the Union of
Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of
Thailand and the Socialist Republic of Vietnam.
Kadang-kadang Mukadimah itu juga dimulai dengan jabatan dari wakil-wakil
yang ikut dalam perundingan. Mukadimah dari the ASEAN Declaration (Bangkok
Declaration) tanggal 8 Agustus 1967, perjanjian yan mendirikan ASEAN mulai
dengan; the Presidium Minister for Political Affairs/Minister for Foreign Affairs of
indonesia, the Deputy Prime Minister of malaysia, the Secretary of Foreign Affairs of
the Philippines...dan seterusnya. Namun perkembangan saat ini tidak lagi
menyebutkan para pihak satu persatu, tetapi sebagai contoh, We, the Foreign
Ministers of the member countries of the Association of Southeast Asian Nations.
Sebagai pengecualian karena lasan-alasan politik, Mukadimah Piagam PBB
dimulai dengan kata-kata; “We, the Peoples of the United Nations....Dalam hal ini
bangsa-bangsa lah yang dianggap sebagai pencipta Piagam PBB dan bukan wakil-
wakil dari negara yang ikut merundingkannya.
Bagi negara-negara Islam, Mukadimah biasanya dimulai dengan puji-pujian
kepada Tuhan.
Selanjutnya Mukadimah juga berisi penjelasan-penjelasan spirit perjanjian. Di
didalamnya juga tercantum pernyataan-pernyataan umum yang kadang-kadang
merupakan program-program politik dari negara-negara peserta. Namun dari segi
hukum, mukadimah tidak mempunyai kekuatan mengikat seperti isi perjanjian itu
sendiri sebagaimana dinyatakan oleh Mahkamah Internasional Tahun 1984 dalam
kasus kegiatan militer dan paramiliter Amerika Serikat di Nicaragua. Mukadimah
45
merupakan dasar moral dan politik dari ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat
dalam batang tubuh suatu perjanjian.
Bagaimana nilai hukum mukadimah suatu perjanjian ? Persoalan ini juga
timbul pada mukadimah yang terdapat dlam Undang-Undang Dasar suatu negara.
Dari segi Hukum Internasional, mukadimah suatu perjanjian tidak mempunyai
kekuatan mengikat walaupun mukadimah tersebut merupakan suatu unsur interpretatif
dari perjanjian, namun mukadimah tetap merupakan dasar moral dan politik dari
ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam batang tubuh seperti halnya dengan
Piagam PBB.
2. Batang Tubuh.
Batang Tubuh suatu perjanjian, berarti “isi perjanjian itu sendiri”. Batang
tubuh ini terdiri dari pasal-pasal yang kadang-kadang jumlahnya cukup banyak,
sebagaio contoh,
Konvensi Wina tentang Hukum perjanjian 1969 (85 pasal); Piagam PBB 1945 (111 pasal): Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (320 pasal); Perjanjian Versailles Tahun 1919 (440 pasal).
3. Klausula Penutup.
Klausula-klausula Penutup juga merupakan bagian dari batang tubuh.
Kalusula-klausula tersebut bukan lagi mengenai isi pokok perjanjian, tetapi
mengenai beberapa mekanisme pengaturan seperti mulai berlakunya perjnjian,
syarat-syarat berlaku, lama berlakunya, amandemen, revisi, aksesi dan lainnya.
4.Annex.
Batang tubuh suatu perjanjian juga dapat dilengkapi dengan Annexes.
Annex berisi ketentuan-ketentuan teknik atau tambahan mengenai satu pasal atau
keseluruhan perjanjian dan terpisah dari perjanjian. Walaupun terpisah tetapi
merupakan satu kesatuan dengan perjanjian dan mempunyai kekuatan hukum yang
sama dengan pasal-pasal perjanjian. Biasanya Annex disusun oleh para ahli dan
dan bila dipisahkan dari perjanjian, itu semata-mata untuk menghindarkan supaya
perjanjian-perjanjian jangan terlalu tebal. Perjanjian Versailles misalnya
46
mempunyai 18 Annex dan kalau disatukan dengan perjanjian itu sendiri yang
terdiri dari 440 pasal, maka tentu perjanjian tersebut akan terlalu tebal. Persetujuan
Marakesh di Marokko, yang membentuk Organisasi Perdagangan Dunia (World
Trade Organisation/WTO), 15 April 1994 mempunyai 6 Annex yang terdiri dari
berbagai kesepakatan dan Memorandum disamping Final Act yang berisikan 23
keputusan dan pernyataan dan ditambah 1 memorandum saling pengertian.
Sekiranya semua unsur ini disatukan dengan batang tubuh perjanjian, tentu akan
sangat tebal dan tidak praktis untuk dibaca.
47