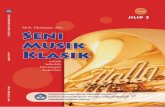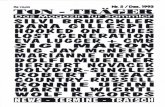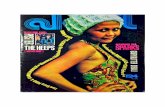BAB_II.pdf - Hak cipta dan penggunaan kembali: Lisensi ini ...
Peranan Lisensi Creative Commons pada Pemasaran Karya Musik Di Indonesia - Fadly Pratama
Transcript of Peranan Lisensi Creative Commons pada Pemasaran Karya Musik Di Indonesia - Fadly Pratama
51
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG MASALAH
Dunia pada hari ini telah menginjak jaman dengan tingkat perkembangan
teknologi yang sangat maju. Hal ini dapat dibuktikan dengan telah merebaknya
teknologi yang bernama internet. Menurut Pew Internet and American Life
Project (Lessig 2004: 8) “58% orang Amerika punya akses Internet pada tahun
2002, atau naik 49% dari dua tahun sebelumnya dan akan meningkat melebihi
dua pertiga bangsa ini pada akhir tahun 2004”. Internet memang sangat
memudahkan masyarakat dunia yang termasuk didalamnya masyarakat
Indonesia, dalam mengakses berbagai kebutuhan dari kebutuhan primer sampai
kebutuhan tersier, seperti makanan hingga barang-barang mewah yang
nantinya akan segera dapat dikonsumsi. Sama dengan yang terjadi pada bentuk
distribusi dan konsumsi karya musik.
Konsumen musik di Indonesia saat ini, telah mengonsumsi karya musik
dalam bentuk digital yang sudah sangatlah mudah diakses lewat internet.
Dibuktikan dengan telah banyaknya penjual-penjual musik online berbasis
internet, sampai dengan festival-festival musik yang disiarkan secara langsung
(live) dan dapat diakses melalui internet (streaming). Sehingga perlindungan
karya musik dalam pemasarannya didalam dunia internet akan dibutuhkan oleh
pihak artis sebagai pelaku/pencipta dan perusahaan rekaman sebagai
manajemen/publisher dari artis tersebut.
Pada aspek ketatanegaraan, pemerintah Republik Indonesia telah
membuat undang-undang yang berkenaan dengan hal tersebut yang tertuang
dalam:
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta,
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987,
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 dan
terakhir diamandemen dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
52
Tetapi dengan disahkannya undang-undang regional Indonesia tersebut
menimbulkan dampak tidak bebasnya pemakaian dan penyebaran karya,
khususnya karya musik dalam peredarannya di ranah internet. Terkesan lebih
mengedepankan “Budaya Komersial” yang merupakan “bagian dari
kebudayaan kita yang diproduksi dan dijual, atau diproduksi untuk dijual”
(Lessig 2004: 9).
Hal tersebut diatas agak bersebrangan dengan asumsi dan perilaku
pengonsumsi karya musik kontemporer yang melakukan penyebaran karya
musik di internet dalam konteks “Budaya Bebas” atau “Free Culture”.
Berdasar pada fenomena tersebut sebuah lembaga di Amerika Serikat
melakukan tindakan dengan membentuk sebuah lembaga dengan nama
Creative Commons. Diikuti oleh Indonesia sebagai anggota dengan nama
Creative Commons Indonesia pada tahun 2009. Lembaga tersebut telah
digagaskan oleh Ari Juliano dan Ivan Lanin sebagai Direktur dan Wakil
Direktur dari Creative Commons Indonesia. Creative Commons mengeluarkan
lisensi berbentuk peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan khusus dalam
mengaplikasikan perlindungan karya musik ala Creative Commons.
Lembaga yang menanungi dan bergerak dalam mendukung
pengaplikasian Creative Commons di Indonesia bernama Wikimedia Indonesia
(surat elektronik dari Ari Juliano, diakses 24 Maret 2014). Tujuan lembaga
tersebut berdiri adalah untuk mengenalkan pada publik Indonesia tentang
Lisensi Creative Commons dan Netlabel (Perusahaan Rekaman/Label Berbasis
Internet; pen) yang pada hari ini telah ikut mendorong tumbuhkembangnya
industri musik pada umumnya dan ranah musik independen khususnya.
Netlabel sendiri adalah sebuah perusahaan rekaman yang merilis karya musik
dari artis dibawah naungannya dalam bentuk digital yang selanjutnya
didistribusikan melalui internet secara “bebas”. Creative Commons Indonesia
bersama Wikimedia Indonesia mengusung dan menerapkan konsep lisensi ala
Creative Commons dalam perkembangan industri musik di Indonesia,
khususnya karya-karya musik yang dirilis secara independen.
53
Di Indonesia khususnya di Bandung, dimana penulis memusatkan
penelitian, penulis telah bertemu dengan salah seorang narasumber yang telah
merilis albumnya melalui internet secara “bebas” sekitar tahun 2006.
Pengertian “bebas” disini bukan bebas secara finansial atau “gratis”.
Melainkan “bebas” disini adalah suatu bentuk sub-kultur yang membebaskan
pencipta dan pemakai karya untuk memakai dan mendistribusikan karya
(khususnya karya musik) secara bebas, tidak terbatas, tetapi dengan
menggunakan lisensi dari pihak pemberi lisensi – lisensi berisi syarat dan
ketentuan yang dikeluarkan oleh Creative Commons.
Oleh karena beberapa hal diatas, penulis tertarik dengan permasalahan
tersebut dan ingin meneliti lebih jauh tentang apa dan bagaimana yang terjadi
pada Creative Commons dan akan memusatkan subyek penelitian pada
lembaga terkait seperti Creative Commons Indonesia, Wikimedia Indonesia,
Indonesian Netlabel Union berikut netlabel-netlabel dibawah naungannya.
Maka dari itu penulis mengangkat tema permasalahan penelitian ini dengan
judul Peranan Lisensi Creative Commons dalam Pemasaran Karya Musik
di Indonesia.
1.2. PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, permasalahan penelitian
ini dapat dikristalisasikan dalam bentuk pertanyaan:
1. Bagaimana cara Creative Commons Indonesia bersama komunitas
dan individu terkait dalam menerapkan bentuk perlindungan karya
menurut syarat dan ketentuan berbentuk lisensi yang dibuat oleh
Creative Commons pada industri musik di Indonesia?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pergerakan Creative
Commons Indonesia dalam penerapan lisensi, serta syarat dan
ketentuan yang dikeluarkan oleh Creative Commons pada industri
musik Indonesia?
54
1.3. TUJUAN PENELITIAN
Tujuan dari penelitian ini yaitu ingin mendapatkan jawaban dari
permasalahan yang ada dalam penelitian, seperti:
1. Mengetahui cara yang ditempuh oleh Creative Commons Indonesia
dan Wikimedia Indonesia bersama Indonesian Netlabel Union dalam
pembuatan, penerjemahan, penyelarasan dan penerapan bentuk lisensi
dan perlindungan menurut lisensi-lisensi, syarat-syarat dan ketentuan-
ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Creative Commons.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan Creative
Commons Indonesia dalam penerapan lisensi-lisensinya pada industri
musik Indonesia.
1.4. MANFAAT PENELITIAN
Setelah penelitian ini selesai dilakukan, diharapkan dapat berguna dan
menjadi bahan masukan bagi:
1. Penulis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman meneliti
tentang pengaruh dan hasil pergerakan yang dilakukan oleh Creative
Commons Indonesia dan Wikimedia Indonesia bersama Indonesian
Netlabel Union terhadap industri musik Indonesia khususnya pada ranah
musik independen.
2. Mahasiswa
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan
wawasan, serta bahan masukan tentang pengaruh dan hasil pergerakan
yang dilakukan oleh Creative Commons Indonesia dan Wikimedia
Indonesia bersama Indonesian Netlabel Union serta beberapa netlabel
dibawah naungan lembaga tersebut terhadap perkembangan industri
musik Indonesia khususnya dalam ranah musik independen terkait lisensi
yang telah dikeluarkan oleh Creative Commons.
55
3. Universitas Pasundan
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif pada
Pendidikan Seni Musik di Universitas Pasundan.
1.5. METODELOGI PENELITIAN
1.5.1. Jenis Penelitian
Metode penelitian adalah cara-cara bekerja untuk dapat
memahami objek penelitian dan merupakan bagian yang penting untuk
diketahui oleh seorang peneliti. Metode penelitian memberikan
ketentuan-ketentuan dasar untuk mendekati suatu masalah dengan tujuan
menentukan atau proses hasil yang benar-benar akurat.
Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, penelitian ini
menggunakan pendekatan naratif deskriptif. Yang nantinya akan
dilanjutkan dengan Teknik Analisis Data dalam Focused Group
Discussion (FGD).
Adapun yang dimaksud dengan Focused Group Discussion yakni
teknik analisis data dengan cara mengumpulkan beberapa orang yang
bersangkutan dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti untuk
menarasikan hingga menyimpulkan beberapa keterangan.
1.5.2. Objek Penelitian
a. Narasumber
Narasumber yang akan dijadikan subjek penelitian adalah
Creative Commons Indonesia sebagai penerjemah, penyelaras dan
penerap sistem lisensi Creative Commons. Wikimedia Indonesia
sebagai yang berperan sebagai penaung Creative Commons
Indonesia beserta netlabel-netlabel dibawahnya yang tersebar di
seluruh wilayah Indonesia. Beberapa narasumber lainnya yang
termasuk didalamnya penggagas lembaga Creative Commons
Indonesia dan artis pengguna lisensi Creative Commons.
b. Waktu
56
Penelitian dilakukan tepat setelah Sidang Proposal Penelitian
Skripsi, yakni mulai petengahan bulan Februari 2014, hingga
sebelum Sidang Skirpsi pada pertengahan Mei 2014.
c. Lokasi
Penelitian dilakukan di beberapa tempat/kediaman/kantor dari
narasumber terkait Creative Commons Indonesia, dan jika
memungkinkan peneliti akan mengikuti Indonesian Netaudio
Festival yang diselenggarakan oleh Indonesian Netlabel Union
dalam kampanyenya tentang Creative Commons pada komunitas-
komunitas juga lembaga pemerintahan.
d. Sumber Data
Sumber data yang didapatkan untuk penelitian ini merupakan
hasil dari proses pengambilan data dari narasumber. Sumber data
ini terdiri dari dua data, yang berasal dari narasumber dan data
dokumen yang relevan dengan penelitian.
1.5.3. Teknik Pengumpulan Data
a. Melakukan observasi ke tempat/kediaman/kantor dari Creative
Commons Indonesia, Indonesian Netlabel Union (tentatif) juga
beberapa kantor dari netlabel dibawah naungan Indonesian
Netlabel Union.
b. Melakukan wawancara dengan pihak narasumber diatas yang
berkaitan dengan perkembangan industri musik Indonesia yang
sesuai dengan masalah yang diteliti.
c. Menganalisis dan mengkaji dokumen yang didapat secara
langsung ataupun dokumen yang diberikan dari pihak
narasumber.
1.5.4. Teknik Analisis Data
57
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
Focus Group Discussion (FGD). Adapun yang dimaksud dengan Focus
Group Discussion adalah teknik analisis data dengan cara mengumpulkan
beberapa orang yang bersangkutan dengan pokok permasalahan yang
sedang diteliti untuk menarasikan hingga menyimpulkan beberapa
keterangan menyangkut pokok permasalahan yang sedang diteliti.
1.6. BATASAN ISTILAH
Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan suatu istilah,
maka penulis memberikan definisi beberapa istilah yang digunakan
pada penulisan ini sebagai berikut:
A. Peranan
Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, peranan adalah orang
atau sesuatu yang menjadi bagian dari suatu masalah atau peristiwa
(W.J.S. Poerwadarminta 2005, 854). Selain itu peranan juga diartikan
sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sesuatu di suatu
peristiwa (W.J.S. Poerwadarminta 2005, 854). Secara umum peranan
diartikan sebagai menjadi bagian atau keikutsertaan.
B. Pemasaran dan Manajemen Pemasaran
Teori pemasaran yang dikemukakan oleh beberapa ahli;
Pemasaran menurut Kotler yang dialihbahasakan oleh
Benyamin Molan (2007, 6) adalah “Suatu proses sosial yang
didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang
mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan,
menawarkan dan secara bebas mempertukarkan produk yang
bernilai dengan pihak lain”
Pemasaran menurut Djaslim Saladin (2007, 1) mendefinisikan
“Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang
dirancang untuk merencanakan harga, promosi dan
mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan
58
keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan
perusahaan.”
Pengertian Manajemen Pemasaran menurut Kotler yang
dialihbahasakan Benyamin Molan (2007, 6) yaitu “Manajemen
pemasaran adalah seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan
mendapatkan, menjaga dan menumbuhkan pelanggan dengan
menciptakan, menyerahkan dan mengkomunikasikan nilai
pelanggan yang unggul”.
Sedangkan menurut Djaslim Saladin (2007, 3) mengemukakan
bahwa manajemen pemasaran sebagai berikut. “Manajemen
Pemasaran adalah analisis, perencanaan, penerapan dan
pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan,
membangun dan mempertahankan pertukaran yang
menguntungkan dengan pasar sasaran dengan maksud untuk
mencapai tujuan – tujuan organisasi”.
Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa manajemen pemasaran
sebagai proses yang mencakup analisis perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian, juga produk atau jasa yang berdasarkan pertukaran dan
bertujuan untuk menghasilkan kepuasan kepada pihak–pihak yang
terlibat di dalamnya.
C. Industri dan Industri Musik
Menurut UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, industri
adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku,
barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai
yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang
bangun dan perekayasaan industri.
Menurut para pakar yang lain;
Tim Grasindo
59
Industri adalah segala macam pekerjaan yang menghasilkan
uang
Badan Pusat Statistik
Industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan
kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa,
terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu dan
mempunyai catatan administrasi sendiri.
Sedangkan jika kita merujuk lagi ke hal yang lebih spesifik yakni
industri musik,
Menurut Wikipedia, industri musik adalah bentuk bisnis dalam
bidang permusikan yang menjual komposisi, rekaman dan
penampilan dari artis atau musisi. Menurut ensiklopedia, industri
musik adalah industri yang melibatkan produksi, distribusi dan
penjualan dari musik dalam bermacam bentuk termasuk promosi
dengan cara pertunjukan langsung. Sedangkan menurut
recordlabelresource.com, industri musik adalah proses produksi
dan komersialisasi musik yang mempunyai suatu yang menarik bagi
khalayak ramai (Widi Asmoro dalam
http://www.widiasmoro.com/2012/06/28/apakah-ada-industri-
musik-di-indonesia/ diakses 17 Maret 2014).
D. Creative Commons dan Lisensi Creative Commons
Creative Commons adalah sebuah organisasi non-profit asal
Mountain View, California, Amerika Serikat yang dimotori oleh Prof.
Lawrence Lessig, dibawah naungan Wikimedia Commons yang
mengeluarkan lisensi bernama sama, yakni Creative Commons.
Organisasi ini bergerak dalam bidang perlindungan karya musik di
ranah internet. Perlindungan tersebut berbentuk lisensi dengan terms &
conditions (syarat dan ketentuan) yang berlaku jika ada karya yang akan
dibagikan secara “bebas” di internet. Lisensi tersebut mengijinkan
penggunaan karya kembali selama mengedepankan sifat-sifat seperti
60
yang tertera pada simbol-simbol yang terdapat pada “lisensi terbuka”
yang dikeluarkan oleh Creative Commons.
Penerapan lisensi dilakukan jika ada karya yang akan dirilis di
internet baik karya tersebut telah didaftarkan pada lembaga hukum
hingga mendapatkan Hak Cipta (Copyright) secara tertulis dan terdaftar
di Direktorat Jendral Hukum Kekayaan Intelektual – di Indonesia,
maupun karya yang tidak pernah didaftarkan ke lembaga hukum
tersebut tetapi tetap ingin menggunakan lisensi dari Creative Commons
sebagai pemberi lisensi dalam ranah internet.
Lisensi tersebut memungkinkan pencipta sebuah karya (seni, sastra
dan ilmu pengetahuan) mendistribusikan karyanya secara “bebas”
kepada para pengguna karyanya. Dengan syarat pengguna/konsumen
tersebut tetap menaati dan menjunjung tinggi bentuk-bentuk lisensi
yang telah dikeluarkan oleh Creative Commons. Adapun bentuk-bentuk
lisensi yang dimaksud adalah sebagai berikut;
61
Gambar 1.1. Bentuk Lisensi yang dikeluarkan oleh Creative Commons dan telah
dialihbahasakan oleh Creative Commons Indonesia (Sumber:
http://creativecommons.org/licenses/?lang=id – diakses pada 18 Maret 2014)
62
1.7. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan ini ditulis bertujuan untuk menjelaskan Bab yang
akan dibuat dalam kerja praktek ini secara jelas dan terarah yaitu sebagai
berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian,
batasan istilah, dan sistematika penulisan.
BAB II LANDASAN TEORI
Bab ini menguraikan mengenai hal yang melandasi atau yang
menjadi dasar perbandingan tentang peranan lisensi Creative Commons
dalam perkembangan industri musik di Indonesia.
BAB III METODELOGI PENELITIAN
Bab ini menguraikan secara detil mengenai metodologi
penelitian yang terdapat didalamnya; jenis penelitian, objek penelitian,
teknik pengumpulan data serta teknik analisis data yang digunakan
dalam membahas dan mengolah data.
BAB IV ANALISIS dan PEMBAHASAN
Bab ini membahas semua hasil penelitian, dari pengumpulan
data, proses di lapangan hingga mendapatkan data dari perkembangan
industri musik yang telah dilakukan oleh Creative Commons Indonesia
beserta lisensinya, bersama dengan Indonesian Netlabel Union dan
beberapa Netlabel dibawah naungannya.
BAB V PENUTUP
Bab ini menyimpulkan keseluruhan isi dari penelitian yang
telah dilakukan juga saran bagi para pihak-pihak dan lembaga-lembaga
terkait seperti Creative Commons Indonesia, Indonesian Netlabel
Union dan Netlabel dibawah naungan Indonesian Netlabel Union.
63
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1. DEFINISI LISENSI
Telah tertulis pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2002 Tentang Hak Cipta, Bab I Pasal 1, poin 14 yang berbunyi:
Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta atau pemegang
Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak
Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.
Adapun pada Bab V – Lisensi;
Pasal 45
(1) Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain
berdasarkan surat perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan
berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
(3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban
pemberian royalty kepada Pemegang Hak CIpta oleh penerima Lisensi.
(4) Jumlah royalty yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta
oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah
pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.
Pasal 46
Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak CIpta tetap boleh
melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga
untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
64
Pasal 47
(1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat
menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau
memuat ketentuan yang menakibatkan persaingan usaha tidak sehat
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
(2) Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga,
perjanjian Lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal.
(3) Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi
yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur
dengan Keputusan Presiden.
Kemudian Hotma (2011) menyatakan,
Beberapa pengertian lisensi yang dikemukakan di atas, maka dapat
dimaknai bahwa yang dimaksud dengan lisensi adalah suatu bentuk
pemberian izin untuk memanfaatkan atau menggunakan suatu Hak Atas
Kekayaan Intelektual, yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada
penerima lisensi agar penerima lisensi dapat melakukan suatu bentuk
kegiatan usaha, baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan (knowhow)
yang dapat dipergunakan untuk memproduksi, menghasilkan, menjual, atau
memasarkan barang (berwujud) tertentu, maupun yang akan dipergunakan
untuk melaksanakan kegiatan jasa tertentu, dengan mmpergunakan Hak Atas
Kekayaan Intelektual yang dilisensikan tersebut. Untuk keperluan tersebut
penerima Lisensi diwajibkan untuk memberikan kontraprestasi dalam bentuk
pembayaran royalti yang dikenal juga dengan License fee.
Dalam ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-
33/Pj/2009 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa
Royalti dari Hasil Karya Sinematografi, lisensi dikatakan sebagai izin yang
diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak
lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk
65
hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu. Di dalam ketentuan ini tujuan
lisensi adalah sebagai salah satu sumber pendapatan Negara, di mana
terhadap royalti yang dibayarkan kepada pencipta atau pemegang hak cipta
dikenakan pajak penghasilan sebagai pendapatan Negara.
Kemudian Wikipedia pada http://id.wikipedia.org/wiki/Lisensi (diakses 28
April 2014),
Lisensi dalam pengertian umum dapat diartikan memberi izin. Pemberian
lisensi dapat dilakukan jika ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang
menerima lisensi, hal ini termasuk dalam sebuah perjanjian. Definisi lain,
pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi
untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan.
Macam Lisensi:
(a) Lisensi atas Hak Kekayaan Intelektual
Salah satu jenis lisensi adalah lisensi atas hak intelektual, misalnya
perangkat lunak komputer. Pemilik lisensi memberikan hak kepada pengguna
untuk memakai dan menyalin sebuah perangkat lunak yang memiliki hak
paten kedalam sebuah lisensi.
Lisensi atas hak intelektual biasanya memiliki beberapa pasal/bagian
didalamnya, antara lain syarat dan ketentuan (term and condition), wilayah
(territory), pembaruan (renewal) dan syarat-syarat lain yang ditentukan oleh
pemilik lisensi.
Syarat dan ketentuan (term and condition): Kebanyak lisensi dibatasi
oleh jangka waktu pemakaian. Hal ini untuk melindungi kekayaan
intelektual dari pemilik lisensi, karena sering atau adanya perubahan
kondisi peraturan pemberian lisensi / pasar. Hal ini juga melindungi
pemilik lisensi dari pemakaian lisensi dengan beberapa alamat IP
66
(Internet Protocol) dalam satu (nomer seri) untuk satu jenis perangkat
lunak.
Wilayah: Pembatasan wilayah adalah batasan pemakaian produk untuk
digunakan dalam satu wilayah atau regional terbatas (tertentu). Sebagai
contoh, sebuah lisensi produk atau jasa untuk daerah atau regional
"Amerika Utara" (Amerika Serikat dan Kanada) tidak dapat dipakai di
Indonesia (regional Asia Tenggara), begitu juga sebaliknya.
(b) Lisensi Massal
Lisensi massal adalah lisensi dari pemilik ke perorangan untuk
menggunakan sesuatu. Contoh; Perangkat Lunak. Rincian lisensi perangkat
lunak biasanya tertuang dalam "Kesepakatan Lisensi Pengguna tingkat
Akhir" (End User License Agreement (EULA).
Dibawah perjanjian "EULA" ini pengguna komputer dapat melakukan
instalasi perangkat lunak dalam satu atau lebih komputer (tergantung
perjanjian lisensi).
(c) Lisensi Merek Barang/Jasa
Pemilik barang atau jasa dapat memberikan izin (lisensi) kepada individu
atau perseroan agar individu atau perseroan tersebut dapat
mendistribusikan (menjual) sebuah produk atau jasa dari pemilik barang
atau jasa dibawah sebuah merek dagang.
Dengan pemakaian lisensi tipe ini, pemakai lisensi dapat menggunakan
(menjual atau mendistribusikan) merek barang atau jasa di bawah sebuah
merek dagang tanpa khawatir dituntut secara hukum oleh pemilik lisensi.
Sebagai contoh, sebuah perusahaan dapat memakai desain dan teknologi
sebuah produk atau jasa yang berasal dari suatu negara dan dipasarkan
dengan memakai nama lain di negaranya sendiri.
67
(d) Lisensi Hasil Seni dan Karakter
Pemilik lisensi dapat memberikan izin atas penyalinan dan
pendistribusian hak cipta material seni dan karakter (misalnya, Mickey
Mouse menjadi Miki Tikus).
(e) Lisensi Bidang Pendidikan
Gelar akademis termasuk sebuah lisensi. Sebuah Universitas
memberikan izin kepada perorangan untuk memakai gelar akademis.
Misalnya (Diploma I (D1), Ahli Madya (Diploma III, (D3)), Sarjana (S1),
Magister (S2), Doktor (S3)).
2.2. DEFINISI CREATIVE COMMONS
Creative Commons, didirikan oleh profesor hukum dari Universitas Stanford,
Lawrence Lessig, bersama dengan rekan-rekannya dari Institut Teknologi
Massachusetts, Universitas Harvard, Universitas Duke dan Universitas Villanova
pada tahun 2001. Dengan Creative Commons, Lessig menyediakan set lisensi hak
cipta gratis untuk digunakan oleh publik. Seorang pencipta yang bersedia untuk
melepaskan karyanya di bawah lisensi Creative Commons (CC) dapat
mengunjungi situs web Creative Commons dan memilih lisensi yang diinginka.
Pemilihan lisensi CC atribusi, misalnya, ia mempertahankan hak cipta, tapi
memungkinkan orang lain untuk menggunakan karya tanpa izin dan tanpa
pembayaran, selama mereka mencantumkan “kredit”nya kepada pencipta yang
asli. Kemudian situs web tersebut menyediakan dengan sendirinya beberapa baris
kode komputer yang nantinya dapat disalin dan ditempelkan di situs web (website)
pencipta, yang ciptaannya ingin dilisensikan oleh CC. Setelah itu, pengunjung situs
web dari pencipta akan melihat logo Creative Commons dan kalimat di bawah logo
yang menunjukkan kondisi dan yurisdiksi yang telah disepakati sebelum
penempelan logo tersebut.
68
2.2.1. Lisensi Creative Commons
Adapun lisensi-lisensi yang dimaksud adalah:
1. CC-BY (Creative Commons - Attribution)
Creative Commons attribution
adalah lisensi yang mengizinkan
orang lain untuk menyalin,
mendistribusikan, menampilkan,
serta membuat karya turunan
berdasarkan suatu karya hanya
jika orang tersebut memberikan
penghargaan pada pencipta atau pemberi lisensi dengan cara yang
disebutkan dalam lisensi. Sebagai contoh anda menemukan video
yang berada dalam domain publik tapi dalam keterangannya video
tersebut lisensinya adalah CC-BY, anda diharuskan memberi
kredit kepada sang pemilik video, biasanya kredit dalam bentuk
Title, Kredit scroll baik di akhir video maupun di awal video.
2. CC-ND (Creative Commons - Non-Derivative)
Creative Commons non-
derivative mengizinkan orang
lain menyalin
mendistribusikan dan
menampilkan hanya salinan
yang sama persis dengan karya
yang akan anda gunakan,
bukan karya turunan dari karya tersebut. Dengan maksud anda
tidak diperbolehkan untuk memodifikasi, mengedit atau meremik
produk file yang anda beli lisensinya.
69
3. CC-NC (Creative Commons - Non-Commercial)
Creative Commons non-
commercial mengizinkan
pengguna lisensi dan
pengguna karya menyalin,
mendistribusikan,
menampilkan, serta
membuat karya turunan
berdasarkan suatu karya hanya untuk tujuan nonkomersial.
Artinya jika anda mengunduh sebuah file video yang lisensinya
CC-NC lalu ingin mereupload ke Youtube anda tidak bisa
menghasilkan uang dari video tersebut.
4. CC-SA (Creative Commons - Share-Alike)
Creative Commons share-
alike mengizinkan orang lain
untuk mendistribusikan
suatu karya turunan hanya di
bawah suatu lisensi yang
identik dengan lisensi yang
diberikan pada karya aslinya.
Sebagai contoh anda ingin
mengabungkan sebuah file video tentang gol-gol dari
pertandingan sepakbola, misalnya gol-gol Cristiano Ronaldo.
Maka di dalam video gol tersebut, anda hanya boleh menggabung
video dari perusahaan televisi yang memberi izin tertulis kepada
anda. Misalnya yang memberi lisensi adalah stasiun televisi “A”,
maka seluruh video golnya semua hanya & harus bersumber dari
stasiun televisi “A”.
70
Perlu diketahui satu orang saja pemegang lisensi melaporkan
video anda mirip dan tidak dapat anda buktikan sudah memiliki
izin lisensi yang sah, fasilitas monetisasi di akun anda bisa
langsung di nonaktifkan oleh pihak penyiar. Kasus ini sering
menimpa kepada pemain adsense salah satu situs siar, Youtube
yang tidak memiliki izin tertulis saat ingin menguangkan video
jenis CC-SA ini. Akibatnya jika sudah terlalu sering melanggar
copyright content, status akun anda langsung bereputasi buruk.
Akun adsense anda pun akan segera terkena banned.
2.2.2. Kombinasi Lisensi Creative Commons
Selanjutnya adalah tampilan dari logo dan lisensi yuridis keluaran
Creative Commons yang telah dikombinasikan dan akan segera dapat
digunakan. Tertuang dalam keterangan berikut ini:
1. Atribusi
CC BY
Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk
menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan, bahkan
untuk kepentingan komersial, selama mereka mencantumkan kredit
kepada Pemilik Ciptaan atas ciptaan asli. Lisensi ini adalah lisensi
yang paling bebas. Direkomendasikan untuk penyebarluasan secara
maksimal dan penggunaan materi berlisensi.
2. Atribusi-BerbagiSerupa (Share-Alike)
CC BY-SA
Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk
menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bahkan
untuk kepentingan komersial, selama mereka mencantumkan kredit
kepada Pemilik Ciptaan dan melisensikan ciptaan turunan di bawah
syarat yang serupa. Lisensi ini seringkali disamakan dengan lisensi
"copyleft" pada perangkat lunak bebas dan terbuka. Seluruh ciptaan
71
turunan dari ciptaan si Pemilik Ciptaan akan memiliki lisensi yang
sama, sehingga setiap ciptaan turunan dapat digunakan untuk
kepentingan komersial. Lisensi ini digunakan oleh Wikipedia, dan
direkomendasikan untuk materi-materi yang berasal dari
penghimpunan materi Wikipedia dan proyek dengan lisensi serupa.
3. Atribusi-TanpaTurunan (Non-Derivative)
CC BY-ND
Lisensi ini mengizinkan penyebarluasan
ulang, baik untuk kepentingan komersial maupun nonkomersial,
selama bentuk ciptaan tidak diubah dan utuh, dengan pemberian
kredit kepada Pemilik Ciptaan.
4. Attribusi-NonKomersial (Non-Commercial)
CC BY-NC
Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk
menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan yang bukan
untuk kepentingan komersial, dan walau mereka harus
mencantumkan kredit kepada Pemilik Ciptaan dan tidak dapat
memperoleh keuntungan komersial, Pengguna Ciptaan tidak harus
melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang sama dengan
ciptaan asli.
5. Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa
CC BY-NC-SA
Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk
menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk
kepentingan komersial, selama Pengguna Ciptaan mencantumkan
72
kredit kepada Pemilik Ciptaan dan melisensikan ciptaan turunan
dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.
6. Atribusi-NonKomersial-TanpaTurunan
CC BY-NC-ND
Lisensi ini adalah lisensi yang paling ketat
dari enam lisensi utama, hanya mengizinkan orang lain untuk
mengunduh ciptaan Pemilik Ciptaan dan membaginya dengan orang
lain selama Pengguna Ciptaan mencantumkan kredit kepada Pemilik
Ciptaan, tetapi Pengguna Ciptaan tidak dapat mengubahnya dengan
cara apapun atau menggunakannya untuk kepentingan komersial.
2.3. DEFINISI NETLABEL
Netlabel adalah label rekaman yang mendistribusikan rilisannya dalam
format digital audio melalui jaringan Internet, rilisan dapat diunduh secara legal
baik gratis maupun berbayar. Idenya adalah menyebarkan musik secara bebas dan
tanpa batas geografis. Netlabel menjadi alternatif dalam wahana musik mandiri di
Indonesia yang saat ini stagnan, dimana jaringan internet belum diantisipasi dengan
baik oleh industri musik arus utama. Yes No Wave Music menyebut netlabel sebagai
aksi “gift economy”, sebuah eksperimentasi dalam menerapkan model musik gratis
kepada pecinta musik di dunia yang kapitalistik ini. Aksi ini bukanlah gagasan
menghancurkan industri musik yang sudah mapan puluhan tahun, tetapi lebih pada
tawaran alternatif dalam mendistribusikan karya musik secara bebas. Bebas untuk
diedarkan, diperdengarkan dan digubah oleh siapa saja. Sebuah pembebasan
kreativitas. Internet telah memberi kita peluang untuk melakukan demokratisasi
‘pasar’. Perubahan teknologi yang begitu cepat tentu saja menimbulkan
overlapping informasi dan menggeser tatanan budaya, sosial dan ekonomi.
Gerakan netaudio mencoba untuk mengkaji wacana tersebut sambil merumuskan
gagasan dan siasat yang tepat.
Adapun lembaga tempat bernaungnya beberapa netlabel di Indonesia adalah
Indonesian Netlabel Union (Serikat Netlabel Indonesia).
73
2.3.1. Indonesian Netlabel Union
Indonesian Netlabel Union (Serikat Netlabel Indonesia) merupakan
satu gerakan kolektif netlabel Indonesia yang ditujukan untuk memulai
jaringan antar-netlabel dan juga untuk mengenalkan kepada publik tentang
eksistensi netlabel lokal serta menjadi sebuah wadah dalam mengkaji wacana
musik di era teknologi informasi. Langkah awal dimulai dengan merilis seri
album kompilasi secara serentak pada tanggal 1 Januari 2011. 5 netlabel aktif
yang turut serta dalam kompilasi tersebut adalah Hujan! Rekords, Inmyroom
Records, Mindblasting, Stone Age Records, dan Yes No Wave Music.
Indonesian Netlabel Union juga menggelar sebuah booth offline sharing dan
merchandise di RRREC Fest #2 di Jakarta, 3-5 Desember 2011. Langkah
kami selanjutnya adalah menyelenggarakan Indonesian Netaudio Festival.
Anitha Silvia (aktifis Indonesian Netlabel Union) dalam blognya
(http://makantinta.blogspot.com/2013/09/tentang-indonesian-netlabel-
union.html) telah menjabarkan beberapa poin mengenai Netlabel.
Kami terbiasa menyebutkan “Indonesian Netlabel Union” daripada
Serikat Netlabel Indonesia. Pada tahun 2007 Netlabel pertama di
Indonesia terbentuk, Yes No Wave Music (meskipun
Tsefula/Tsefuelha Records telah melakukannya di tahun 2006, akan
tetapi Yes No Wave Music mempopulerkannya di Indonesia.
Tsefula/Tsefuelha kemudian menjadi sub-label dari Yes No Wave
Music) yang kemudian disusul oleh beberapa Netlabel lain pada
tahun-tahun berikutnya.
Indonesian Netlabel Union dicetuskan oleh Wok The Rock (juga
sebagai pencetus dari Yes No Wave Music), beliau mengajak 4
Netlabel lainnya (Stone Age Records, Hujan Rekords, Mindblasting,
Inmyroom Records) untuk membuat suatu jaringan antar-netlabel
yang berfungsi menyebarkan ide mengenai Netlabel di Indonesia.
Indonesian Netlabel Union diproklamirkan pada 1 Januari 2011,
ditandai dengan membuat rilisan pada tanggal yang bersamaan.
74
Konsep “Netlabel” di ranah industri musik Indonesia masih asing.
Indonesian Netlabel Union percaya bahwa konsep Netlabel akan
menjadi suatu alternatif yang signifikan dalam model distribusi
musik. Melalui Indonesian Netlabel Union para aktifis melakukan
sosialisasi mengenai Free Culture, dimana musik adalah salah satu
produk budaya yang dimiliki bersama.
Adapun proses penyatuan dari beberapa Netlabel di Pulau Jawa
menurut Silvia dalam makantinta (2013), ialah:
Pada sesi pertama (1 Januari 2011), 5 Netlabel pastinya cukup
mudah dikoordinasikan karena mereka sudah saling mengenal dan
punya visi yang sama. Saya sebagai penikmat rilisan Netlabel, sangat
tertarik dengan Indonesian Netlabel Union, yang kemudian pada saat
yang bersamaan saya dan 5 Netlabel tersebut membuat rilisan
bersama.
Pada sesi kedua, saya baru menemukan tantangan. Pada
pertengahan tahun 2011 saya mengusulkan offline gathering untuk
pegiat/penikmat Netlabel kepada Indonesian Netlabel Union, ide ini
disambut dengan hangat. Saya dengan cukup mudah mengumpulkan
semua aktivitis Netlabel, karena mereka aktif di dunia maya,
berkorespondensi via surat elektronik dan berbagi ide mengenai
offline gathering. Salah satu tantangan adalah saya harus rajin
berbagi pengetahuan mengenai Netlabel (dan Free Culture secara
garis besar) kepada banyak orang yang penasaran dengan ide offline
gathering dan Netlabel. Tantangan lain adalah mengumpulkan
mereka untuk bertemu tatap muka membahas proyek ini karena kami
tersebar di berbagai kota di Pulau Jawa.
Kemudian setelah sejumlah korespondensi via surat elektronik dan
tatap muka dengan Wok The Rock, acara offline gathering diberi
tajuk Indonesian Netlabel Festival. Kemudian seiring dengan
75
berkembangnya ide, Silvia (Indonesian Netlabel Union) bersama
Wok (The Rock) merubah nama acara menjadi Indonesian Netaudio
Festival (INF). Karena konten acara yang dimaksud adalah tidak
hanya berbentuk perayaan untuk merayakan terbentuknya Netlabel,
tapi semua aktivitas berbagi musik via Internet. Praktik Netlabel
(mengunggah musik kemudian menyebarkannya secara gratis) sudah
banyak dilakukan meskipun tanpa Netlabel, maka Indonesian
Netlabel Union dengan Yes Nowave Music memilih konsep Netaudio.
Selanjutnya Anitha Silvia menjadi ketua panitia Indonesian Netaudio
Festival 2012. Kami mengaktifkan Indonesian Netlabel Union
sebagai sebuah HUB, menjadi wadah para penggiat dan penikmat
free-music, berbagi berbagai ilmu pengetahuan dan ilmu industri
musik, hingga membuat logo Indonesian Netlabel Union.
Kemudian untuk Visi dan Misi yang digunakan oleh Indonesian
Netlabel Union, ialah:
Visi: Menjadi HUB antar-Netlabel di Indonesia
Misi: Mensosialisasikan maksud dan tujuan dari Netlabel di
Indonesia
Adapun tujuan dari Indonesian Netlabel Union, adalah:
Indonesian Netlabel Union berbagi pengetahuan dan pengalaman
mengenai Netlabel dan aktivitas yang terkait dengannya kepada
penggiat/penikmat musik di industri musik Indonesia. Netlabel
adalah alternatif dari model distribusi karya bukan saingan dari
beberapa model label rekaman lain. Netlabel mendistribusikan musik
bagus (menurut kurator masing-masing Netlabel) dengan lebih efektif
dan tepat sasaran.
76
2.4. DEFINISI PEMASARAN
2.4.1. Definisi Manajemen Pemasaran
Pemasaran merupakan studi kasus tentang proses pertukaran
bagaimana transaksi dimulai, dimotivasikan, dimungkinkan dan diselesaikan.
Pemasaran membicarakan tentang bagaimana manusia dan organisasi dapat
mengelola lebih baik kegiatan mereka untuk menghasilkan laba. Kegiatan
pemasaran dalam suatu perusahaan merupakan fungsi bisnis yang langsung
berhadapan dengan aktifitas konsumen untuk bertransaksi dengan
perusahaan. Kegiatan pemasaran merupakan suatu aktifitas sosial yang luas
dan semua jenis pemasaran menggunakannya dalam berbagai cara yang
berbeda-beda.
Adapun fungsi pemasaran adalah untuk menarik dan
mempertahankan pelanggan, serta mengungguli pesaing dengan memenuhi
dan memuaskan kebutuhan pelanggan. Pemasaran dapat didefinisikan
sebagai kegiatan pemasar untuk menjalankan bisnis (profit dan non profit)
guna memenuhi kebutuhan pasar dengan barang ataupun jasa, menetapkan
harga, mendistribusikan, serta mempromosikannya melalui proses
pertukaran, agar memuaskan konsumen dan mencapai tujuan perusahaan
(Budiarto: 1993).
Menurut Kotler (2000), pemasaran merupakan suatu proses sosial dan
manajerial yang didalamnya terdapat individu dan kelompok yang
mendapatkan apa saja yang dibutuhkan dan diinginkan dengan menciptakan,
menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain.
Pemasaran merupakan proses perencanaan dan pelaksanaan rencana,
77
penerapan harga, promosi dan distribusi dari ide, barang dan jasa untuk
menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan individu dan tujuan
organisasi (The American Marketing Association).
Berhasil tidaknya dalam pencapaian tujuan bisnis tergantung pada
keahlian di bidang pemasaran, produksi, keuangan, maupun bidang lain.
Selain itu juga tergantung pada kemampuan untuk mengkombinasikan
fungsi-fungsi tersebut, agar organisasi dapat berjalan lancar. Menurut Umar
(2003) pengertian pemasaran adalah kegiatan yang meliputi keseluruhan
sistem yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan usaha yang bertujuan
merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan
barang-barang atau jasa yang akan memuaskan kebutuhan pembeli, baik yang
aktual maupun potensial.
Selain itu, ada beberapa teori pemasaran lain yang dikemukakan oleh
ahli;
Pemasaran menurut Kotler yang dialihbahasakan oleh Benyamin
Molan (2007: 6) adalah “Suatu proses sosial yang didalamnya
individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan
dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan secara
bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain”
Pemasaran menurut Djaslim Saladin (2007: 1) mendefinisikan
“Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang
dirancang untuk merencanakan harga, promosi dan
mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan
keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan.”
Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa manajemen pemasaran
sebagai proses yang mencakup analisis perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian, juga produk atau jasa yang berdasarkan pertukaran dan
bertujuan untuk menghasilkan kepuasan kepada pihak–pihak yang terlibat di
dalamnya.
Konsep dan teori pemasaran pada saat ini mengalami perkembangan
yang sangat pesat seiring dengan bertambah majunya peradaban umat
78
manusia yang ditandai oleh era globalisasi yang sedang berjalan, dengan
indikator-indikatornya seperti perkembangan teknologi, pasar bebas,
pendewasaan regulasi dalam bidang ekonomi, dan lain-lain. Hal ini
dikarenakan pemasaran merupakan sebuah konsep teori praktis yang
menuntut keselarasan teori yang harus terus berubah sehingga sesuai dengan
praktek di dunia nyata yang juga sangat berkembang pesat.
Adapun beberapa teori pemasaran yang dikemukakan oleh beberapa
ahli. Pemasaran menurut Kotler yang dialihbahasakan oleh Benyamin Molan
(2007: 6) adalah:
Suatu proses sosial yang didalamnya terdapat individu dan kelompok
sedang berproses dalam mendapatkan apa yang mereka butuhkan
dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan secara bebas
mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain
Kemudian pemasaran menurut Djaslim Saladin (2007: 1),
mendefinisikan:
Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang
dirancang untuk meremcanakan harga, promosi, dan
mendistribusikan barang – barang yang dapat memuaskan keinginan
dan mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan.
Pengertian Manajemen Pemasaran menurut Kotler yang
dialihbahasakan Benyamin Molan (2007: 6) yaitu:
Manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu memilih pasar sasaran
dan mendapatkan, menjaga dan menumbuhkan pelanggan dengan
menciptakan, menyerahkan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan
yang unggul.
Sedangkan Djaslim Saladin (2007: 3), mengemukakan bahwa
manajemen pemasaran sebagai berikut:
79
Manajemen Pemasaran adalah analisis, perencanaan, penerapan
dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan,
membangun dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan
dengan pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan –
tujuan organisasi.
Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa manajemen pemasaran
sebagai proses yang mencakup analisis perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian, juga produk atau jasa yang berdasarkan pertukaran dan
bertujuan untuk menghasilkan kepuasan kepada pihak–pihak yang terlibat di
dalamnya.
2.4.2. Bauran Pemasaran
Menurut Djaslim Saladin (2007: 3) bauran pemasaran adalah
“serangkaian dari variabel pemasaran yang dapat dikuasai oleh perusahaan
dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam pasar sasaran”.
Sedangkan menurut Kotler yang dialihbahasakan oleh Benyamin
Molan (2007: 23), Bauran Pemasaran adalah “seperangkat alat pemasaran
yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya”.
Kotler yang dialihbahasakan oleh Benyamin Molan (2007: 17)
mengklasifikasikan empat unsur dari alat–alat bauran pemasaran yang terdiri
atas 4P dalam pemasaran barang, diantaranya adalah: produk (product), harga
(price), tempat (place), promosi (promotion),
Adapun pengertian dari masing-masing variabel bauran pemasaran
tersebut akan dijelaskan dibawah ini:
1. Produk (product)
80
Produk merupakan unsur terpenting dalam bauran pemasaran
yang memiliki berbagai macam arti dan makna, namun secara umum
produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk
diperhatikan, dibeli, digunakan dan dikonsumsi. Istilah produk
mencakup benda fisik, jasa, kepribadian, tempat, organisasi, atau ide.
Keputusan-keputusan mengenai produk mencakup kualitas,
kestimewaan, jenis merk, kemasan, pengembangan, bersarkan
penelitian pasar, pengujian dan pelayanan pra dan purna jual.
Produk menurut Stanton yang dikutip oleh Buchari Alma
(2007:139), merupakan seperangkat atribut baik berwujud maupun
tidak berwujud, termasuk di dalamnya masalah warna, harga, nama
baik pabrik, nama baik toko yang menjual (pengecer), dan pelayanan
pabrik serta pelayanan pengecer yang diterima oleh pembeli guna
memuaskan keinginannya.
2. Harga (Price)
Merupakan unsur terpenting kedua dalam bauran pemasaran
setelah produk dan merupakan satu-satunya unsur dalam bauran
pemasaran yang menghasilkan pendapatan penjualan, sedangkan
unsur-unsur lainnya merupakan pengeluaran biaya saja. Keputusan-
keputusan mengenai harga mencakup tingkat harga, potongan harga,
keringanan periode pemasaran, dan rencana iklan yang dibuat oleh
produsen.
Harga menurut Oka A. Yoeti dalam Ratih Hurriyati (2008: 51)
harga dapat diartikan sebagai suatu jumlah uang yang harus
dipersiapkan seseorang untuk membeli atau memesan suatu produk
yang diperlukan atau diinginkannuya.
Penentuan harga merupakan titik kritis dalam bauran pemasaran
karena hargamenentukan pendapatdari suatu usaha. Disamping itu
81
juga hargamerupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang
merupakan penerimaan penjualan, sedangkan unsur lainnya
merupakan unsur biaya apa saja. Keputusan penentuan harga juga
sangat signifikan dalam penentuan nilai atau manfaat yang dapat
diberikan kepada pelanggan dan memainkan peranan penting dalam
gambaran kualitas produk.
3. Tempat (Place)
Menunjukkan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh produsen
untuk menjadikan suatu produk yang dihasilkan dapat diperoleh dan
tersedia bagi konsumen pada waktu dan tempat yang tepat dimanapun
konsumen berada.
Di dalam industri manufaktur tempat (place) diartikan sebagai
saluran distribusi, two level channesl zero channel, dan multilevel
channel, sedangkan produk untuk industri jasa menurut Ratih
Hurriyati (2008: 55) tempat diartikan sebagai tempat pelayanan yang
digunakan dalam pemasok kepada pelanggan yang dituju merupakan
keputusan kunci, keputusan mengenai lokasi pelayanan yang akan
digunakan melibatkan pertimbangan dimana penyerahan jasa kepada
pelanggan dan dimana itu akan berlangsung. Tempat juga penting
sebagai lingkungan dimana dan bagaimana suatu produk akan
diserahkan sebagai bagian dari nilai dan manfaat.
4. Promosi (Promotion)
Merupakan berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan dengan
tujuan utama untuk menginformasikan, membujuk, mempengaruhi
dan mengingatkan konsumen agar membeli produk dari perusahaan.
82
Dalam hal ini keputusan-keputusan yang diambil mencakup iklan,
penjualan personal, promosi penjualan, dan publikasi.
Pemasaran memerlukan alat komunikasi yang berguna untuk
memperkenalkan produknya kepada pasar sasaran. Promosi
merupakan alat komunikasi antara produsen dan konsumen. Menurut
Buchari Alma (2007: 179) “promosi merupakan sejenis komunikasi
yang memberikan penjelasan yang meyakinkan calon konsumen
tentang barang dan jasa. Tujuan promosi adalah memperoleh
perhatian, mendidik, mengingatkan, dan meyakinkan calon
konsumen”.
Adapun empat komponen bauran pemasaran yang telah dijelaskan
dapat digambarkan seperti di bawah ini.
Gambar 2.1. Konsep 4 P dalam Bauran Pemasaran
(Sumber: Kotler Dialihbahasakan Benyamin Molan, 2005: 18)
Bauran Pemasaran
Pasar Sasaran
Keragaman Produk Kualitas
Design Ciri
Nama Merk Kemasan
Ukuran Pelayanan
Garansi Imbalan
Saluran Pemasaran Cakupan Pasar Pengelompokkan Lokasi Persediaan Transportasi
Daftar Harga Rabat/Diskon
Potongan Harga khusus
Periode Pembayaran Syarat kredit
Promosi Penjualan Periklanan Tenaga Penjualan Public Relation Pemasaran Langsung
Product Place
Promotion Price
83
Pemasaran terdiri dari strategi bauran pemasaran (marketing mix)
dimana organisasi atau perusahaan mengembangkan untuk
mentransfer nilai melalui pertukaran untuk pelanggannya. Kotler dan
Armstrong (2008: 62) berpendapat bahwa, “bauran pemasaran
(marketing mix) adalah kumpulan alat pemasaran taktis terkendali
yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respons yang
diinginkannya di pasar sasaran”. Marketing mix terdiri dari empat
komponen yang sering disebut dengan ”empat P (4P)”, yaitu Product
(Produk), Price (Harga), Place (Tempat), dan Promotion (Promosi).
Dari penjelasan tersebut dapat digambarkan ke dalam bentuk
(Gambar 2.2.) yang memperlihatkan alat pemasaran masing-masing
P.
Gambar 2.2. Empat P Bauran Pemasaran
(Sumber: Philip Kotler dan Gary Armstrong. (2008). Prinsip-prinsip Pemasaran. Edisi
Ke-12 Jilid 1. Jakarta: Erlangga)
2.4.3. Komunikasi Pemasaran
Jika digabungkan, komunikasi pemasaran merepresentasikan
gabungan semua elemen dalam bauran pemasaran, yang memfasilitasi
pertukaran dengan menargetkan merek untuk sekelompok pelanggan, posisi
Place
Product
Price Promotion Target Market
84
merek yang membedakan dengan merek pesaing, dengan menciptakan suatu
arti yang disebarluaskan kepada pelanggannya (Chitty, 2011: 3). Kotler dan
Keller (2012: 498) menyatakan bahwa, “Marketing communications are
means by which firms attempt to inform, persuade, and remind comsumers –
directly or indirectly – about the products and brands they sell”. Artinya,
Komunikasi pemasaran adalah sarana yang digunakan perusahaan dalam
upaya untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen
baik secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang
mereka jual.
Marketing communication dapat didefinisikan sebagai kegiatan
pemasaran dengan menggunakan teknik-teknik komunikasi yang bertujuan
untuk memberikan informasi kepada khalayak agar tujuan perusahaan
tercapai, yaitu terjadinya peningkatan pendapatan atas penggunaan jasa atau
pembelian produk yang ditawarkan (Kennedy dan Soemanagara, 2006: 5).
Penggabungan kajian pemasaran dan komunikasi akan menghasilkan
kajian baru yang disebut marketing communication (komunikasi pemasaran).
Marketing communications merupakan bentuk komunikasi yang bertujuan
untuk memperkuat strategi pemasaran, guna meraih segmen pasar yang lebih
luas.
Perusahaan menggunakan berbagai bentuk komunikasi pemasaran
untuk mempromosikan apa yang mereka tawarkan dan mencapai tujuan
finansial. Kegiatan pemasaran yang melibatkan aktivitas komunikasi meliputi
iklan, tenaga penjualan, papan nama toko, display ditempat pembelian,
kemasan produk, direct-mail, sampel produk gratis, kupon, publisitas, dan
alat-alat komunikasi lainnya. Secara keseluruhan, aktivitas-aktivitas yang
disebutkan di atas merupakan komponen promosi dalam bauran pemasaran
(marketing mix) (Shimp, 2003: 4).
2.4.4. Direct Marketing
85
Direct Marketing (pemasaran langsung) adalah hubungan secara
langsung dan membangun hubungan dengan pelanggan yang langgeng –
penggunaan surat langsung, telepon, televisi, respons langsung, e-mail,
Internet, dan sarana lain untuk berkomunikasi secara langsung dengan
konsumen tertentu. (Kotler dan Armstrong, 2008: 117). Definisi direct
maketing menurut Belch dan Belch yang dikutip oleh Kennedy dan
Soemanagara (2006: 26), ”direct marketing is a system of marketing by which
organizations communicate directly with the target consumer to generate a
response or transaction.” Belch dan Belch menggambarkan adanya suatu
hubungan yang sangat dekat dengan pasar sasaran dan memungkinkan
terjadinya proses komunikasi dua arah. Dipahami bahwa komunikasi
langsung bertujuan untuk memperoleh respons atau transaksi yang terjadi
secara langsung dalam waktu singkat. Direct marketing dapat mencapai
tujuan itu dengan dukungan faktor-faktor lain yaitu:
1) Bahwa pasar sasaran telah mengenal produk dan layanan
sebelumnya melalui saluran media massa atau media promosi
lainnya.
2) Bahwa pasar sasaran yang dituju merupakan hasil penyaringan
dari proses segmentasi yang selektif, sehingga pasar sasaran yang
dipilih adalah mereka yang mewakili kedekatan dengan produk
dan layanan yang ditawarkan.
3) Bahwa pemasar atau komunikator telah menyiapkan informasi
yang lengkap sesuai dengan apa yang dibutuhkan, dan
kemungkinan jawaban atas serangkaian informasi mengenai
produk dan layanan yang ditawarkan (solusi).
4) Bahwa direct marketing juga merupakan sebuah proses yang
memberikan kesempatan pada pasar sasaran untuk menilai dan
menimbang suatu informasi atau produk dalam suatu proses
86
pengambilan keputusan, memungkinkan proses komunikasi
dilakukan berulang-ulang. Proses ini biasa disebut proses follow
up (follow up process).
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa direct marketing
dilaksanakan sebagai cara untuk bertemu dengan konsumen setelah muncul
respons dari pasar atas informasi produk yang telah disebarkan pada
konsumen. Informasi disebarkan melalui beberapa cara, yaitu melalui iklan
di surat kabar, televisi, majalah, internet atau media massa lainnya. Tetapi
penyebaran informasi juga dapat dilakukan melalui pengiriman brosur atau
leaflet lewat pos (direct mail).
Follow up process merupakan bentuk pendekatan direct marketing,
melalui direct mail atau melalui telemarketing. Yang dimaksud telemarketing
dan direct marketing adalah dengan penggunaan fasilitas teknologi tinggi
dengan dua jenis pasar sasaran, yaitu personal target dan group target.
Personal target biasanya berbentuk layanan informasi langsung pada pemilik
situs jejaring atau e-mail yang tertuju pada personal. Disampaikan dengan
pemberian informasi singkat tentang alat pemuas kebutuhan dan ajakan untuk
lebih rinci mempelajari kualitas produk dan layanan, manfaat, harga yang
dapat dinegosiasikan, dan bagaimana memperoleh produk itu. Group target,
merupakan follow up yang terjadi melalui fasilitas teknologi, dimana tersedia
media yang dapat mendukung komunikasi personal to group (PTG), dan
bentuk teknologi yang memungkinkan hal ini terjadi adalah melalui
konferensi. (Kennedy dan Soemanagara, 2006: 27).
Follow up dapat terjadi didasarkan pada dua kondisi, yaitu
1) follow up dilakukan setelah proses direct mailing, dengan
berhubungan langsung pada contact person. Hubungan ini dapat
berlangsung melalui proses tatap muka dan telepon. Follow up
dilakukan setelah kunjungan langsung ke pasar sasaran potensial,
yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan di antara
keduanya.
87
2) follow up dilakukan setelah respons atas informasi yang disebar
melalui media massa ata media lainnya. Proses ini lebih mudah
dan lebih efektif karena respons muncul disebabkan adanya
ketertarikan akan produk dan layanan dalam memenuhi
kebutuhan mereka, sehingga terdapat penghematan biaya telepon
secara langsung.
2.5. DEFINISI MUSIK
Musik adalah bunyi yang diatur menjadi pola yang dapat menyenangkan
telinga kita atau mengkomunikasikan perasaan atau suasana hati. Musik
mempunyai ritme, melodi, dan harmoni yang memberikan kedalaman dan
memungkinkan penggunaan beberapa instrumen atau bunyi-bunyian. Seperti yang
diungkapkan Bernstein & Picker (1972) bahwa:
musik adalah suara-suara yang diorganisasikan dalam waktu dan memiliki
nilai seni dan dapat digunakan sebagai alat untuk mengekspresikan ide dan
emosi dari komposer kepada pendengarnya.
Musik adalah seni penataan bunyi secara cermat yang membentuk pola
teratur dan merdu yang tercipta dari alat musik atau suara manusia. Musik biasanya
mengandung unsur ritme, melodi, harmoni, dan warna bunyi (Syukur: 2005).
Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa musik adalah bunyi yang diatur
menjadi sebuah pola yang tersusun dari bunyi atau suara dan keadaan diam (sounds
and silences) dalam alur waktu dan ruang tertentu dalam urutan, kombinasi dan
hubungan temporal yang berkesinambungan sehingga mengandung ritme, melodi,
warna bunyi, dan keharmonisan yang biasanya dihasilkan oleh alat musik atau
88
suara manusia yang dapat menyenangkan telinga dan mengekspresikan ide,
perasaan, emosi atau suasana hati.
2.5.1. Karya
a) Karya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
pekerjaan; hasil perbuatan; buatan; ciptaan (terutama hasil
karangan).
b) Sebuah perbuatan seseorang atau beberapa orang atau
organisasi/lembaga yang menghasilkan sesuatu produk atau jasa.
Karya merupakan bentuk tindakan nyata setelah proses oleh cipta
dan rasa serta diniati "berbuat sesuatu untuk membuahkan hasil".
Sedangkan jika kita merujuk lagi ke hal yang lebih spesifik yakni
industri musik,
Menurut Wikipedia, industri musik adalah bentuk bisnis dalam
bidang permusikan yang menjual komposisi, rekaman dan
penampilan dari artis atau musisi. Menurut ensiklopedia, industri
musik adalah industri yang melibatkan produksi, distribusi dan
penjualan dari musik dalam bermacam bentuk termasuk promosi
dengan cara pertunjukan langsung. Sedangkan menurut
recordlabelresource.com, industri musik adalah proses produksi dan
komersialisasi musik yang mempunyai suatu yang menarik bagi
khalayak ramai (Widi Asmoro dalam
http://www.widiasmoro.com/2012/06/28/apakah-ada-industri-musik-
di-indonesia/ diakses 17 Maret 2014).
89
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1. DEFINISI DAN JENIS PENELITIAN
Penelitian adalah suatu proses dari langkah-langkah yang digunakan untuk
mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk meningkatkan pemahaman
tentang suatu topik atau masalah (Creswell 2012: 3). Penelitian ilmiah
didefinisikan sebagai aplikasi dari metode dan teknik yang sistematik yang
membantu peneliti dan praktisi untuk memahami dan meningkatkan suatu proses
(pembelajaran/pengajaran). Menurut Emzir (2011: 6), peneliti kualitatif sering
dikatakan mengambil pendekatan induktif untuk mengumpulkan data karena
mereka merumuskan hipotesis hanya setelah mereka mulai melakukan observasi,
wawancara, dan analisis dokumen.
Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan
menggunakan jalur pendekatan induktif yang sangat dekat diasosiasikan dengan
pendekatan penelitian kualitatif, yang dalam pengaplikasiannya, penulis
mengumpulkan lalu merangkum data dengan menggunakan metode naratif atau
verbal: observasi, wawancara, dan analisis dokumen.
90
Denzin & Lincoln (1994: 2) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai
berikut; Penelitian kualitatif adalah multi metode dalam fokus, melibatkan
pendekatan interpratif, dan naturalistik pada materi subjeknya. Ini berarti peneliti
kualitatif melakukan penelitian dalam latar alamiah, berusaha memahami atau
menafsirkan fenomena dalam istilah-istilah makna yang diberikan orang
terhadapnya.
Penelitian kualitatif melibatkan studi menggunakan dan mengumpulkan
variasi materi empiris – studi kasus, pengalaman pribadi, introspektif, cerita
kehidupan, teks wawancara, observasi, sejarah, interaksional, dan teks visual –
yang mendeskripsikan momen rutin dan problematik serta makna dalam kehidupan
individual.
Adapun pendekatan lain yang penulis gunakan untuk melengkapi data dari
penelitian kualitatif yang telah dibahas diatas, yakni penelitian naratif. Penelitian
Naratif adalah;
3.1.1. Definisi dan Latar Belakang Penelitian Naratif
Terma naratif (narrative) muncul dari verba “to narrate” yang
artinya menceritakan atau mengatakan (to tell) suatu cerita secara detil.
Dalam disain penelitian naratif, peneliti mendeskripsikan kehidupan
individu, mengumpulkan, mengatakan cerita tentang kehidupan individu, dan
menuliskan cerita atau riwayat pengalaman individu tertentu. Lebih jelasnya,
penelitian naratif berfokus pada kajian seorang individu.
Dalam Cresswell (2004: 53) menyatakan, penelitian naratif
mempunyai banyak bentuk dan berakar dari disiplin ilmu kemanusiaan dan
sosial yang berbeda. Naratif bisa berarti terma yang diberikan pada teks atau
wacana tertentu atas bentuk penyelidikan dalam penelitian kualitatif. Naratif
dipahami sebagai sebuah teks tertulis atau lisan yang memberikan sebuah
catatan tentang suatu kejadian, peristiwa atau rangkaian kejadian, dan
rangkaian peristiwa yang dihubungkan secara kronologis.
3.1.2. Tipe-tipe Kajian Naratif
91
Jika seorang peneliti berencana melaksanakan kajian naratif maka ia
perlu mempertimbangkan tipe kajian naratif yang akan dilaksanakannya.
Pendekatan pertama yang digunakan dalam penelitian naratif adalah
membedakan tipe penelitian naratif melalui strategi analisis yang digunakan
oleh pengarang (Cresswell 2007: 54). Polkinghorne dalam Cresswell (2007:
54) menyebutkan strategi tersebut menggunakan paradigma berpikir untuk
menghasilkan deskripsi tema yang menggenggam sekaligus melintasi cerita
atau sistem klasifikasi tipe cerita. Analisis naratif ini menekankan peneliti
untuk mengumpulkan deskripsi peristiwa atau kejadian dan kemudian
mengkonfigurasikannya ke dalam cerita menggunakan sebuah alur cerita
(plot).
Chase dalam Cresswell (2007: 55) menyajikan pendekatan yang tidak
jauh berbeda dengan definisi analisis naratif milik Polkinghorne. Chase
menyarankan bahwa peneliti boleh menggunakan alasan paradigmatik untuk
kajian naratif, seperti bagaimana individu dimampukan dan dipaksa oleh
sumberdaya sosial, disituasikan secara sosial dalam penampilan interaktif dan
bagaimana pencerita membangun interpretasi.
Pendekatan kedua, menekankan pada ragam bentuk yang ditemukan
dalam praktik-praktik penelitian naratif. Dibawah ini akan disajikan ragam
contoh bentuk penelitian naratif.
FIGURE 15.1 Tabel 3.1.Contoh Bentuk Penelitian Naratif. Sumber; Educational Research: Planning,
Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (2004) oleh John W.
Cresswell
Examples of Types of Narrative Research Forms
•Autobiographies
• Biographies
• Life Writing
• Personal Accounts
• Personal Narratives
• Narrative Interviews
• Personal Documents
• Documents of Life
• Life Stories and Life Histories
• Oral Histories
• Ethnohistories
• Ethnobiographies
• Autoethnographies
• Ethnopsychologies
• Person-centered Ethnographies
• Popular Memories
• Latin American Testimonies
• Polish Memoirs
92
3.1.3. Prosedur Melaksanakan Penelitian Naratif
Langkah-langkah melaksanakan penelitian naratif menurut Cresswell
(2007: 55) adalah sebagai berikut:
1. Menentukan problem penelitian atau pertanyaan terbaik yang
tepat untuk penelitian naratif. Penelitian naratif adalah penelitian
terbaik untuk menangkap cerita secara detil atau pengalaman
kehidupan terhadap kehidupan tunggal atau kehidupan sejumlah
individu.
2. Menyeleksi satu atau lebih individu yang memiliki cerita atau
pengalaman kehidupan untuk diceritakan dan menghabiskan
waktu (sesuai pertimbangan) bersama mereka untuk
mengumpulkan cerita mereka melalui tipe majemuk informasi.
3. Mengumpulkan cerita tentang konteks cerita tersebut.
4. Menganalisa cerita partisipan dan kemudian menceritakan ulang
(restory) cerita mereka ke dalam kerangka kerja yang masuk akal.
Restorying adalah proses organisasi ulang cerita ke dalam
beberapa tipe umum kerangka kerja. Kerangka kerja ini meliputi
pengumpulan informasi, penganalisaan informasi untuk elemen
kunci cerita (misalnya: waktu, tempat, alur, dan scene/adegan)
dan menulis ulang cerita guna menempatkan mereka dalam
rangkaian secara kronologis.
5. Berkolaborasi dengan partisipan melalui pelibatan aktif mereka
dalam penelitian. Mengingat para peneliti mengumpulkan cerita,
maka mereka menegosiasikan hubungan, transisi yang halus dan
menyediakan cara yang berguna bagi partisipan.
93
3.1.4. Tantangan
Karakteristik dan prosedur penelitian naratif yang dipaparkan di atas
memunculkan tantangan. Peneliti perlu mengumpulkan informasi yang luas
tentang partisipan. Peneliti juga perlu mempunyai pemahaman yang jelas
terhadap konteks kehidupan seorang individu. Dibutuhkan mata yang tajam
untuk mengidentifikasi sumber materi yang dikumpulkan tentang cerita
tertentu yang mampu menangkap pengalaman seorang individu.
3.2. TEKNIK PENELITIAN
Adapun teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni teknik
observasi, studi literature, wawancara dan Focus Group Discussion dengan
penjelasan sebagai berikut:
1. Observasi
Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan
langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata, tanpa
ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut (Nazir 1983:
212). Penulis melakukan observasi secara langsung untuk mendapatkan data
atau informasi mengenai objek yang akan diteliti baik pengamatan langsung
atau tidak langsung. Adapun hal-hal yang akan diobservasi oleh peneliti
adalah dengan menganalisis kegiatan promosi dan sosialisasi lain yang
dilakukan oleh Creative Commons Indonesia, faktor-faktor apa saja yang
mempengaruhi promosi dan sosialisasi Creative Commons Indonesia dalam
menerapkan lisensi Creative Commons pada industri musik Indonesia, serta
pengaruh positif dan negatif dari publik terhadap gagasan dan lisensi yang
94
telah dikeluarkan dan disosialisasikan oleh Creative Commons Indonesia
sebagai tambahan.
2. Studi Literatur
Studi literatur adalah salah satu teknik yang dilakukan untuk
mendapatkan data atau informasi melalui buku-buku bacaan, artikel, koran,
jurnal, skripsi, tesis dan pemaparan lainnya dalam bentuk tulisan yang
memiliki korelasi dengan topik penelitian yang akan dibahas. Sumber bacaan
yang akan dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah mengenai
manajemen pemasaran pada sebuah lembaga dan bentuk tulisan lain terkait
dengan bentuk-bentuk promosi dan sosialisasi yang telah dilakukan oleh
lembaga yang sedang penulis teliti.
3. Wawancara
Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan
penelitian dengan teknik tanyajawab pada narasumber, baik secara langsung
maupun tidak langsung” (Soeharto 1993: 114). Adapun responden atau
narasumber yang di wawancarai adalah tokoh-tokoh yang dianggap memiliki
kompetensi di dalam memberikan informasi mengenai objek penelitian.
Seperti direktur dan wakil direktur Creative Commons Indonesia, pengurus
dan anggota tetap dari Wikimedia Indonesia, Indonesian Netlabel Union,
netlabel serta artis-arits/pencipta-pencipta dibawahnya. Proses wawancara ini
di pergunakan untuk mengetahui latar belakang perusahaan dan untuk
mengetahui strategi manajemen pemasaran lembaga-lembaga tersebut diatas.
95
4. Focus Group Discussion
Focus Group Discussion (FGD) adalah diskusi berbentuk forum terfokus
pada sebuah masalah. FGD disebut juga group interview. Tergolong dalam
jenis wawancara terfokus atau terstruktur. FGD secara sederhana dapat
didefinisikan sebagai suatu diskusi yang dilakukan secara sistematis dan
terarah atas suatu isu atau masalah tertentu. Minichiello (1990: 90)
mengemukakan, wawancara jenis ini menggunakan panduan diskusi
tersusun tetapi urutan pertanyaannya tidak disusun secara kaku. FGD
menurut Hoed (1995, 1), dirancang dengan tujuan mengungkapkan persepsi
kelompok mengenai suatu masalah.
Menurut Krueger (1988, 93), ada beberapa teori agar FGD dapat berjalan
dengan baik. Teori tersebut adalah;
A = Attention (perhatian)
I = Interest (minat)
D = Desire (hasrat)
D = Decision (keputusan)
A = Action (aksi, kegiatan)
Peserta FGD pada kesempatan ini adalah penulis, beberapa pimpinan
lembaga hingga pemakai lisensi dari lembaga terkait, yakni Creative
Commons, Indonesian Netlabel Union serta beberapa netlabel-nya. Diskusi
ini bertujuan memusatkan satu pokok permasalahan kemudian masing-
masing pihak diatas menarasikan apa-apa saja yang telah dilakukan selama
perjalanan dan masa perkembangan pada lembaganya masing-masing dalam
mengembangkan dan mensosialisasikan pokok masalah yang diangkat oleh
penulis yakni lisensi yang dikeluarkan oleh Creative Commons. Hingga pada
akhirnya forum tersebut bisa memberikan data-data dan keterangan terkait
masalah yang sedang penulis teliti.
96
3.3. LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN
Untuk menguji kebenaran informasi, penulis melaksanakan beberapa langkah
sebagai berikut:
Pra Pelaksaan Penelitian
1. Survey
Langkah pertama yang penulis lakukan dalam proses penyelesaian
laporan skripsi ini adalah mengobservasi data melalui internet, dimana
semua lalu lintas data dalam hal pensosialisasian, pemromosian dan
pemasaran, beserta data-data penting lain mengenai Creative Commons
Indonesia berada di internet. Terbukti bahwa dengan melalui surat
elektronik (bertukar email dengan Ari Juliano – Direktur Creative
Commons Indonesia dan Anitha Silvia – Perwakilan Indonesian Netlabel
Union, lalu mengunjungi situs-situs yang berkenaan dengan Creative
Commons Indonesia, penulis sudah mendapatkan banyak informasi,
dikarenakan semua pergerakan Creative Commons dan Indonesian Netlabel
Union memang selalu dilaporkan dan dibagikan (share) via internet
(Twitter, Blog, dll). Informasi tersebut termasuk didalamnya adalah alamat
kantor dari sdr. Ari Juliano (Bang Ajo) sebagai direktur utama Creative
Commons Indonesia yakni di Assegaf Hamzah & Partners, Menara
Rajawali Lantai 16, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Pusat dan alamat
kantor dari sdri. Anitha Silvia sebagai perwakilan Indonesian Netlabel
Union yang berbasis di Surabaya.
Selama proses penulisan dan perumusan judul skripsi, penulis juga telah
melakukan observasi terdahulu ke salah satu pemakai lisensi Creative
Commons Indonesia yakni sdr. Angkuy (Anggung “Kuy Kay” Suherman)
dari duo elektronik Bottlesmoker bertempat di DAGO500 Jalan Ir. H.
Juanda nomor 500, Bandung, Jawa Barat.
97
2. Menentukan Judul dan Topik Penelitian
Setelah bertemu dan melakukan diskusi dan observasi dengan sdr.
Angkuy dari Bottlesmoker, langkah penulis selanjutnya yakni menentukan
judul penelitian yang sesuai dengan topik dan rumusan masalah penelitian
yang telah ditentukan. Penulis juga terlebih dahulu melakukan konseling
dengan Dosen Pembimbing Dua tentang hasil diskusi dan observasi yang
telah penulis lakukan dengan sdr. Angkuy dari Bottlesmoker. Dari beberapa
judul penelitian yang penulis ajukan, maka judul yang disetujui oleh Dosen
Pembimbing Dua tersebut ialah “Peranan Lisensi Creative Commons
dalam Pemasaran Karya Musik di Indonesia”.
3. Pembuatan Proposal
Setelah judul topik disetujui, langkah selanjutnya adalah menyusun
proposal untuk mempersiapkan sidang proposal. Kegiatan ini dilakukan
melaui bimbingan langsung dengan pembimbing I dan II dengan judul dan
topik penelitian yang telah disetujui oleh dewan skripsi.
Persiapan Penelitian
Dalam tahap pelaksanaan penelitian ini penulis mengikuti prosedur sebagai
berikut;
1. Pengumpulan Data
Tahap selanjutnya yaitu pengumpulan data, baik dari sumber tertulis
maupun dari narasumber yang telah di tentukan sebelumnya. Pengumpulan
data di lakukan selama 6 bulan mulai dari bulan mei 2013 sampai bulan
oktober 2013.
2. Konsultasi dengan Dosen Pembimbing
98
Proses bimbingan dengan pembimbing I dan pembimbing II dilakukan
mulai dari pembuatan proposal penelitian, sampai menjelang ujian sidang.
3. Pengolahan Data
Untuk menguji kebenaran informasi data dilakukan pengolahan data
yang di peroleh dari hasil observasi dan wawancara dikumpulkan untuk
dianalisis dan di sesuaikan dengan kepentingan penelitian. Uraian yang
diperoleh kemudian di susun secara sistematis untuk dijadikan bahan
laporan.
Adapun langkah – langkah dalam megolah data, yakni;
1. Menyusun Data
Data dan informasi yang telah diperoleh, disusun menurut tata
urutan langkah-langkah menganalisis data penelitian. Dalam
menyusun data, masalah-masalah yang perlu diperhatikan adalah
menyeleksi dan menyaring informasi sesuai dengan kebutuhan dari
sub-bahasan yang telah dirumuskan.
2. Menyingkronisasikan antara data di lapangan dengan literatur
tertulis dari para ahli.
3. Menarik Kesimpulan
Menarik kesimpulan adalah kegiatan akhir dari penulisan laporan,
data yang telah disusun dari pengolahan data, hasilnya kemudian
disusun bab-per-bab yang dituangkan dalam kerangka tulisan
sebagai laopran penelitian. Kegiatan selanjutnya adalah membuat
kesimpulan berdasarkan keseluruhan pengelolaan data dari tulisan
pada bab I sampai bab V.
4. Penyusunan Laporan Penelitian
Dalam penyusunan laporan penelitian disusun secara lengkap dan
benar dari halaman judul, bab I sampai bab V tetapi sebelum
99
penyusunan laporan berbentuk tulisan, terlebih dahulu diadakan
proses kegiatan bimbingan dengan pembimbing I dan pembimbing
II. Beranjak dari penyusunan laporan, proses selanjutnya yakni
melakukan proses penggandaan laporan penulisan yang telah
disetujui oleh pembimbing I dan pembimbing II.
3.4. INSTRUMEN PENELITIAN
Alat-alat yang digunakan oleh penulis selama masa observasi, penulisan dan
penganalisaan data yang telah penulis dapatkan dari narasumber terkait karya tulis
ini ialah;
1. Komputer (Personal Computer dan Laptop). Penulis menggunakan
media tersebut dalam menulis dan mengumpulkan data berkaitan dengan
karya tulis ini. Media ini telah digunakan oleh penulis sejak pertama ide
menulis karya tulis ilmiah ini tercetus hingga pada saat terakhir sidang
skripsi.
2. Alat Dokumentasi (untuk foto, video dan merekam suara). Media ini
digunakan secara berkala dan berkesinambungan, berkaitan dengan
metodologi penelitian yang diambil oleh penulis yakni Naratif Deskriptif.
Penelitian naratif deskriptif membutuhkan data yang bisa dibuktikan
validasi dan keabsahnnya secara tangibel dan intangible. Baik secara
visual maupun verbal. Yang selanjutnya harus penulis representasikan
dihadapan penguji.
3. Koneksi Internet. Media ini sangat dibutuhkan oleh penulis dalam
mencari data yang berkaitan dengan subyek penulisan karya ilmiah ini,
dikarenakan media ini menyimpan banyak sekali data dan sudah
100
dijadikan media distribusi dan dokumentasi dari tiap-tiap kegiatan yang
dilakukan oleh subyek penelitian.
BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1. HASIL DATA
4.1.1. Creative Commons Internasional
Sejarah Singkat
Creative Commons, didirikan oleh profesor hukum dari Universitas
Stanford, Lawrence Lessig, bersama dengan rekan-rekannya dari
Institut Teknologi Massachusetts, Universitas Harvard, Universitas
Duke dan Universitas Villanova pada tahun 2001. Dengan Creative
Commons, Lessig menyediakan set lisensi hak cipta gratis untuk
digunakan oleh publik. Seorang pencipta yang bersedia untuk
melepaskan karyanya di bawah lisensi Creative Commons (CC) dapat
mengunjungi situs web Creative Commons dan memilih lisensi yang
diinginkan dalam satu kali klik.
101
Dengan mengunjungi laman web resmi Creative Commons di
http://creativecommons.org/choose/?lang=id, anda akan diberitahu
bagaimana cara anda sebagai pencipta, jika ingin mendapatkan Lisensi
Creative Commons untuk karya anda. Adapun pengetahuan singkat
mengenai Lisensi terdapat pada situs yang sama, pada laman
http://creativecommons.org/licenses/?lang=id.
Pemilihan lisensi CC atribusi, misalnya, ia mempertahankan hak
cipta, tapi memungkinkan orang lain untuk menggunakan karya tanpa
izin dan tanpa pembayaran, selama mereka mencantumkan “kredit”nya
kepada penciptaan yang asli. Kemudian situs web tersebut menyediakan
dengan sendirinya beberapa baris kode komputer yang nantinya dapat
disalin dan ditempelkan di website pencipta, yang ciptaannya ingin
dilisensikan oleh CC. Setelah itu, pengunjung situs web dari pencipta
akan melihat logo Creative Commons dan kalimat di bawah logo yang
menunjukkan kondisi dan yurisdiksi yang telah disepakati sebelum
penempelan logo tersebut.
Berikut ini adalah tampilan dari logo dan lisensi yuridis keluaran
Creative Commons yang dimaksud:
102
Gambar 4.1. Lisensi dan Lambang keluaran Creative Commons Internasional dalam
bahasa Inggris (sumber: http://creativecommons.org, diakses tanggal 08 April 2014)
Creative Commons telah menarik beberapa respon positif dan
semakin populer. Diperkirakan bahwa 5 juta item telah tersedia di
bawah lisensi CC per Oktober 2004 (“Movement Seek”, 2004), dan
terdapat 145 juta kreasi telah terdaftar sampai Juni 2006 (Rohter, 2006).
Banyak berita telah ditulis tentang penggunaan dan keberhasilan lisensi
CC (misalnya, Chmielewski, 2004; "Movement Seek" 2004; Rohter,
2006). Sejumlah akademisi juga telah mencatat potensi Creative
Commons untuk melayani kepentingan publik (Gasaway, 2003; Jones,
2004; Merges, 2004, O'Hara, 2003; Reichman & Uhlir, 2003; Stoeltje,
2004, Wagner, 2003).
Penelitian ini mengadaptasi kerangka berpikir Kim (2005). Secara
singkat, kerangka teoritis tersebut berpendapat bahwa ada dua visi
bersaing dari dasar-dasar hukum hak cipta: yakni "visi milik pribadi –
private property” dan "visi kebijakan publik – public policy vision”.
Visi milik pribadi tercetus karena adanya kelompok yang mendukung
103
dan percaya bahwa hak cipta berasal dari alam sebagai hak milik penulis
(pencipta), dan bahwa penulis yang membuat karya asli berhak untuk
memiliki hak milik atas pekerjaan mereka. Penekanan visi milik pribadi
adalah pada kepentingan pribadi si penulis (pencipta) dalam
mengendalikan penggunaan karya cipta sebagai milik si penulis
(pencipta). Visi kebijakan publik, sebaliknya, diadakan oleh mereka
yang mencatat hak cipta yang secara historis berkembang sebagai hibah
didalam masyarakat dari monopoli terbatas, dan yang berpikir bahwa
hak-hak pencipta harus mempertimbangkan kebebasan orang lain untuk
menggunakan karya berhak cipta. Visi ini disebut visi kebijakan publik,
karena menggarisbawahi pentingnya kepentingan publik dalam
mengakses dan menggunakan karya berhak cipta. Hal ini juga
menggarisbawahi peran hak cipta sebagai suatu kebijakan publik yang
bertujuan untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara kepentingan
pribadi dan kepentingan umum.
Kedua visi bersaing tersebut diatas telah bentrok dalam
perkembangan hukum hak cipta selama 300 tahun, tetapi konflik antara
mereka telah meningkat di era digital ini. Advokat dari visi milik pribadi
berharap bahwa teknologi digital akan memungkinkan pemegang hak
cipta untuk mengumpulkan biaya untuk setiap penggunaan hak cipta
karya-karya mereka (Goldstein, 2003). Sebaliknya, mereka mengamati
pelanggaran hak cipta besar-besaran. Penyedia konten, termasuk
industri musik, telah putus asa untuk melembagakan mekanisme
penegakan yang kuat terhadap “penyalinan” untuk melindungi
kepemilikan mereka.
Pendukung visi kebijakan publik berharap bahwa teknologi digital
akan meningkatkan produksi dan pembagian dalam produk budaya
(Benkler, 2000; Kranich, 2004). Sebaliknya, mereka mengamati bahwa
hukum hak cipta kontemporer telah menjadi begitu ketat, sehingga
104
beresiko menghambat kreativitas dan inovasi masa depan. Sebagai
contoh, Samuelson (n.d.) menyatakan bahwa
pada industri besar hak cipta hari ini, substansi hukum
dikhawatirkan mengalami kehilangan kontrol atas materi berhak
cipta karena perkembangan teknologi, karena sebelumnya para
pemegang hak cipta mendapatkan lebih banyak kontrol konsumen
dibandingkan dengan sebelumnya.”
Demikian pula, Boyle (2004) menulis bahwa
kebijakan properti kekayaan intelektual kontemporer ada "didalam
goncangan hebat dari 'hak budaya (rights-culture)' yang mengarah
kepada debat sesat (Kim 2007: 187).
Kelahiran Creative Commons erat kaitannya dengan kekhawatiran
bahwa upaya pemegang hak cipta untuk melindungi kepemilikan hak
cipta material mereka, secara tidak langsung mengancam kebebasan
pengguna. Salah satu pemimpin Creative Commons Internasional,
Lessig, telah mencatat bahwa
hukum hak cipta telah banyak mengalami perubahan (2004b), juga
berpendapat bahwa telah terjadi pergeseran dari "budaya bebas”
- “free culture” menjadi budaya “membatasi dan memberikan izin”
- “a restrictive, permission culture” (2004a). Budaya bebas
maksudnya bebas dalam arti "kebebasan", “freedom”, bukan
dalam arti "tidak ada pembayaran". Digunakan orang untuk
memiliki kebebasan untuk membuat, menggunakan sumber daya
budaya (cultural resources), untuk mengkritik orang lain dengan
menggunakan kultur di sekitar mereka. Namun, Lessig menyatakan
bahwa "kebebasan mereka semakin menaikan tingkat pembatasan.
105
Dan pertanyaannya menjadi, Bagaimana kita menanggapinya?"
(2004b, hal 10).
Kemudian secara berkesinambungan membuat Lessig dan beberapa
individu yang memiliki “visi kebijakan publik” menyarankan Creative
Commons, yang memiliki visi "untuk membangun sebuah lapisan yang
wajar, hak cipta fleksibel dalam menghadapi aturan baku yang semakin
ketat" (Some Rights Reserved, n.d.).
4.1.2. Jajaran Direksi dan Dewan Penasihat
Penggagas Creative Commons Internasional sendiri adalah Lawrence
Lessig, James Boyle dan Hal Abelson. Dibentuk pada Desember 2002 (Kim,
2007: 187). Agar lembaga ini lebih kuat dan mapan, maka Creative Commons
yang sebelumnya hanya sebuah proyek kecil dari Wikimedia Foundation,
kemudian mulai pada tahun terciptanya Creative Commons, 2002 hingga
sekarang, Creative Commons Internasional (CC HQ) tengah merekrut beberapa
orang, yakni;
4.1.2.1. Jajaran Direksi
Hal Abelson, seorang professor lulusan
Computer Science and Engineering. Beliau
adalah seorang pemenang Several Teaching
Award di Institut Teknologi Massachusetts
(MIT) – Cambridge. Beliau juga adalah salah
satu anggota dari Institute of Electrical and Electronics Engineers
(IEEE).
106
Paul Brest, adalah profesor emeritus dan mantan
dekan dari Stanford Law School yang baru saja
kembali setelah bertugas selama 12 tahun sebagai
Presiden di William and Flora Hewlett
Foundation. Bersama dengan Profesor Deborah
Hensler, beliau sedang mengembangkan hukum dan kebijakan
laboratorium publik di Sekolah Hukum. Beliau juga merupakan Wakil
Dekan di Fakultas Stanford Center on Philanthropy and Civil Society.
Menerima gelar Artium Baccalaureus (B.A.) di Swarthmore College
pada tahun 1962 dan Legum Baccalaureus (LL.B) di Harvard Law
School pada tahun 1965. Beliau menjabat sebagai petugas hukum untuk
Hakim Bailey Aldrich dan Hakim Agung John M. Harlan. Beliau juga
membuka kantor praktek bersama dengan NAACP Legal Defense and
Educational Fund, Inc. di Jackson, Mississippi yang mengurusi litigasi
hak-hak sipil. Pada tahun 1969, beliau bergabung dengan fakultas
Stanford Law School, dimana beliau mendapatkan gelar Kenneth and
Harle Montgomery Professor of Public Interest Law. Penelitian dan
pengajaran beliau terfokus pada hukum konstitusi yang kemudian
membuat beliau menuliskan beberapa artikel tentang penafsiran
konstitusi, diskriminasi ras dan tindakan afirmatif. Dari tahun 1987
hingga 1999, beliau menjabat sebagai dekan di Stanford Law School
dan mempelopori perluasan kurikulum Bisnis, Hukum Lingkungan,
Teknologi Tinggi, Negosiasi, dan memimpin kampanye dengan modal
sebesar 115,000,000 US$. Beliau juga menjadi penulis dari Money Well
Spent: A Strategic Guide to Smart Philanthropy (Bloomberg Press,
2008); Problem Solving, Decision Making and Professional Judgement
(Oxford University Press, 2010) dan Processes of Constitutional
Decision Making: Cases And Materials (Aspen Publishers , 2006).
107
Ben Adida, adalah direktur teknik di Square, Inc.
Memiliki keinginan sangat besar dalam
menggunakan teknologi untuk memberdayakan
masyarakat. Ben Adida telah lama bekerja dalam
bidang online payments & identity, secure voting,
catatan kesehatan pribadi (personal health records), pekerja Web. Dia
telah mengembangkan perangkat lunak bebas (Free Software) selama
15 tahun dan perangkat lunak Web selama 18 tahun. Sebelumnya, Ben
Adida adalah direktur teknik di Mozilla dan Fakultas Penelitian di
Harvard Medical School. Dia adalah Chief Technology Officer Creative
Commons pada saat peluncuran Creative Commons pada tahun 2002.
Ben menerima gelar Ph.D. di Institut Teknologi Massachusetts (MIT)
jurusan Cryptography and Information Security.
Renata Avila, adalah pejuang Hak Asasi Manusia
dan Pengacara Kekayaan Intelektual di
Guatemala, ia juga pengacara untuk kebebasan
berekspresi (freedom of expression), privasi
(privacy), akses informasi (access to information)
dan hak-hak adat (indigenous rights). Renata Avila memimpin Creative
Commons afiliasi Guatemala dan anggota dari Web Index Science
Council. Saat ini beliau juga telah memimpin kampanye "Web We
Want”, yang bertujuan untuk mengagendakan hak asasi manusia yang
positif bagi pengguna internet.
Diane Cabell, Sekretaris Perusahaan untuk
Creative Commons. Pendiri Clinical Program in
Cyberlaw di Berkman Center for Internet &
Society dimana beliau menjabat sebagai Asisten
Direktur. Praktek hukumnya berfokus pada
perusahaan nirlaba berbasis web yang sekaligus menjabat sebagai
panelis sengketa ranah nama (domain name dispute panelist) untuk
108
World Intellectual Property Organization (WIPO). Berbasis di
Portsmouth, New Hampshire, beliau saat ini menjabat sebagai direktur
di iCommons Ltd, sebuah badan amal Inggris yang didirikan oleh
Creative Commons pada tahun 2005.
Michael W. Carroll, adalah Visiting Professor
of Law di Washington College of Law di
Washington, Washington DC. Dimulai pada
September 2009, beliau bergabung di Fakultas
dan menjadi Direktur Program Keadilan
Informasi dan Kekayaan Intelektual (Director of the Program On
Information Justice and Intellectual Property. Ajaran dan ketertarikan
ilmiahya terfokus pada kekayaan intelektual dan hukum internet. Beliau
telah menjadi anggota dari Dewan Creative Commons sejak tahun 2001
dan telah menjadi anggota dari subset Direksi yang mengkampanyekan
Sains Commons dan ccLearn. Sebelum memasuki pengajaran hukum,
beliau adalah seorang pengacara yang memfokuskan diri pada properti
intelektual dan isu seputar internet di Washington D.C. office of Wilmer,
Cutler & Pickering. Beliau juga menjabat sebagai petugas hukum untuk
Hakim Judith W. Rogers dari United States Court of Appeals for the
District of Columbia Circuit dan Hakim Joyce Hens Green dari United
States District Court for the District of Columbia. Beliau menerima
gelar Sarjananya (A.B.) dengan general honors dari University of
Chicago dan J.D. magna cum laude dari Georgetown University Law
Center. Sebelum memasuki sekolah hukum, beliau bekerja sebagai
jurnalis, guru sekolah menengah atas di Zimbabwe dan Program
Officer for Democracy and Governance Projects di Afrika.
109
Eric Saltzman, Lulus pada tahun 1972 dari
Harvard Law School, Eric F. Saltzman memulai
karirnya sebagai pengacara pertahanan kriminal
(criminal defense attorney) di kantor pertahanan
sipil Seattle dan Boston. Sembari mengajar di
Harvard Law School jurusan Criminal Trial Advocacy, beliau
mengambil kelas pembuatan film di MIT. Beliau juga yang
mengenalkan kamera ke ranah pengadilan dengan membuat film
berjudul The Shooting of Big Man: Anantomy of a Criminal Case.
Kepada CBS News, beliau memproduseri dan mendireksi investigasi
kasus Miami: The Trial That Sparked the Riots. Sebuah investigasi yang
tentang seorang petugas kepolisian yang melakukan bunuh diri. Pada
pertengahan tahun 1980, beliau berpindah ke bisnis film dan mulai
mengumpulkan dan melisensikan perpustakaan gambar bergerak klasik
dan hak pertelevisian untuk mulai menggunakan media seperti kabel,
microwave dan transmisi satelit. Pada tahun 2000-2002, beliau
menjabat sebagai Direktur Eksekutif di Harvard’s Berkman Center for
Internet & Society.
Molly Van Houweling, mengawali karir sebagai
Direktur Eksekutif Creative Commons dan
anggota dari Center for Internet & Society di
Standford Law School. Beliau juga bekerja
sebagai asisten professor di Unversity of Michigan
Law School. Setelah lulus pada bulan Juni 1998 dari Harvard Law
School, beliau bekerja sebagai editor artikel di Harvard Journal of Law
& Technology. Salah seorang anggota dari Berkman Center for Internet
& Society at Harvard Law School dan menjadi anggota staff pertama di
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).
Kemudian beliau menjabat sebagai petugas hukum untuk Hakim
110
Michael Boudin dari United States of Appeals for the First Circuit dan
Justice David Souter of the United States Supreme Court.
4.1.2.2. Dewan Penasehat
Jimmy Wales, salah satu penggagas Wikimedia
Foundation, sebuah koperasi non-profit yang
mengoperasikan Wikipedia dan beberapa proyek
wiki lainnya. Beliau juga penggagas dari lembaga
for-profit, Wikia, Inc.
Brian Fitzgerald, adalah seorang Professor of
Intellectual Property and Innovation dari
Queensland University of Technology (QUT) di
Brisbane, Australia. Beliau memegang kelas di
pascasarjana hukum di Oxford University dan
Harvard University. Pada tahun 1998-2002 beliau menjadi pimpinan
dari School of Law and Justice at Southern Cross University di New
South Wales, Australia. Pada Januari 2002 sampai Januari 2007 beliau
ditunjuk sebagai pimpinan dari School of Law at QUT di Brisbane,
Australia. Semenjak 2004 beliau telah menjadi pimpinan proyek dari
Creative Commons Australia. Beliau memiliki komitmen kuat kepada
para kreator dan komunitas teknologi sehingga pada tahun 2010 beliau
telah mendirikan klinik hukum yang menyediakan saran hukum bagi
artis setempat dan permulaan bagi yang tidak dapat membayar untuk
perlakuan hukum.
111
Lawrence Lessig, Roy L. Furman Professor of
Law di Harvard Law School dan sebagai
pengarah (director) di Edmond J. Safra Center for
Ethics di Harvard University. Sebelum bergabung
kembali di Stanford Law School, beliau terlebih
dahulu menjadi penggagas dari School’s Center for Internet and Society
di University of Chicago. Beliau adalah anggota dari Member of the
American Academy of Arts and Sciences, the American Philosophical
Association dan penerima beberapa penghargaan, termasuk
penghargaan Free Software Foundation’s Freedom Award, Fastcase 50
Award dan menjadi salah satu dari Scientific American’s Top 50
Visionaries. Beliau mendapatkan B.A. di jurusan ekonomi dan B.S. di
jurusan manajemen dari University of Pennsylvania dan M.A. di jurusan
philosophy dari Cambridge dan J.D. dari Yale.
Pada hari ini Creative Commons bersama lisensinya telah tersebar
dan diterapkan di lebih dari 100 negara dan 70 wilayah yuridiksi,
termasuk Indonesia. Negara-negara pengguna lisensi keluaran Creative
Commons disebut dengan negara afiliasi Creative Commons. Dari data
yang penulis dapatkan dari hasil observasi dengan salah seorang aktifis
Creative Commons afiliasi Indonesia bahwa, afiliasi-afiliasi tersebut
sebelumnya harus memiliki lembaga yang sudah mapan, yang nantinya
bisa menaungi Creative Commons dalam ranah hukum dan ranah
pendistribusian karya.
Lisensi Creative Commons berkemungkinan memiliki beberapa
perbedaan dalam penerapannya pada masing-masing negara dan
wilayah yuridis. Hal tersebut dikarenakan setiap negara dan wilayah
yuridis masing-masing memiliki poin-poin yang berbeda baik dalam hal
“karya-karya yang dilindungi” maupun bentuk dan bunyi hak cipta
masing-masing negara dan wilayah yuridis itu sendiri.
Adapun karya-karya yang dapat dilisensikan oleh Creative
Commons adalah;
112
1. Teks,
2. Gambar (foto, ilustrasi, dan desain),
3. Audio (musik dan pidato),
4. Video (film dan cuplikan),
5. Lain-lain (software, alat komputer, dll).
Secara lebih mendalam, Creative Commons juga menyertakan
beberapa detil untuk karya-karya didalam internet yang bermuatan teks.
Seperti contohnya, Blog yang bermuatan teks saja, atau blog dengan
beberapa foto terkait dengan teks didalamnya. Adapun jenis dari karya
tersebut yakni;
1. Blog (teks saja): sebuah blog dengan entri teks;
2. Blog (teks dengan foto): sebuah blog yang terdiri dari entri teks
tetapi juga memiliki beberapa foto yang cocok dengan entri teks;
3. Situs Web: baik situs Web yang hanya terdiri dari teks atau
website yang terdiri baik teks dan gambar yang cocok beberapa;
4. Teks lain: buku (e-book), artikel, esai, novel, dan dokumentasi
perangkat lunak, dan
5. Pendidikan Bahan: sebuah website dengan rencana pelajaran
atau paket saja. (Wikipedia dalam Creative_Commons, diakses
pada 09 April 2014)
Adapun menurut pandangan para pakar terhadap Creative
Commons, meskipun Creative Commons disarankan oleh pendukung
visi kebijakan publik, tampaknya memiliki potensi untuk menyelesaikan
konflik mendidih antara dua visi hukum hak cipta (Boyle 2004: 0009).
Untuk menjadi solusi, sesuatu harus memenuhi tiga kondisi:
Pertama, harus secara akurat mencerminkan cara orang
menghasilkan karya kreatif, kedua, harus melayani kepentingan
pribadi pencipta, dan ketiga, harus melayani kepentingan umum
pengguna. (Kim 2007: 13(1)).
113
Kemudian cara melisensikan suatu karya dengan lisensi Creative
Commons adalah sebagai berikut:
a. Web Resmi Creative Commons
Calon pengguna lisesnsi Creative Commons dapat mengunjungi
web resmi Creative Commons di http://creativecommons.org/,
kemudian memilih opsi Licenses – Choose a Licenses. Kemudian
calon pengguna akan diarahkan ke laman web dengan tampilan
sebagai berikut (http://creativecommons.org/choose/?lang=id):
Gambar 4.2. Kolom pertanyaan dan pemilihan lisensi Creative Commons (sumber:
http://creativecommons.org/choose/?lang=id, diakses tanggal 30 Mei 2014)
114
1. Kolom pertama (kiri atas) menunjukkan dua buah pertanyaan
dasar kepada calon pengguna lisensi.
2. Kolom kedua (kanan atas) menunjukkan bentuk lisensi yang
telah dipilih dan disesuaikan dengan pertanyaan dasar pada
kolom pertama.
3. Kolom ketiga (kiri bawah) menunjukkan keterangan lengkap
dan kolom pengisian keterangan lebih lanjut, atas karya dari
calon pengguna. Kolom ini membantu membuat metadata yang
terbaca oleh komputer dilengkapi dengan keterangan lebih
lanjut seperti:
judul ciptaan,
nama pencipta,
jaringan atau tautan yang berhubungan dengan pencipta,
tautan terkait pencipta,
bentuk ciptaan (terdapat opsi: Bentuk Lainnya/Berbagai
Bentuk, Suara, Video, Gambar, Teks, Data Set,
Interaktif), dan
tanda lisensi (calon pengguna dapat membiarkannya
seperti asal (default) untuk web kontemporer)
4. Kolom keempat (kanan bawah) menunjukkan tautan yang dapat
disalin pada web calon pengguna lisensi Creative Commons,
berbentuk kode HTML (HyperText Markup Language), bahasa
markah yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web
(Wikipedia: http://id.wikipedia.org/wiki/HTML, diakses 30 Mei
2014)
b. Situs Soundcloud
Calon pengguna lisensi Creative Commons yang telah
menggunakkan situs berbagi Soundcloud, dapat dengan mudah
menjumpai kolom persetujuan penggunaan lisensi Creative
115
Commons setelah pengunggahan karya musik dalam kolom
Upload.
Gambar 4.3. Tampilan beranda dari situs Soundcloud (sumber: https://soundcloud.com/,
diakses tanggal 30 Mei 2014)
Kemudian calon pengguna lisensi Creative Commons akan
diarahkan ke laman https://soundcloud.com/upload-beta. Setelah
karya yang sudah berbentuk data digital terunggah, kemudian calon
pengguna lisensi Creative Commons akan diarahkan ke laman
keterangan lisensi karya, dengan tampilan:
116
Gambar 4.4. Kolom pemilihan lisensi Creative Commons pada situs Soundcloud
(sumber: http://soundcloud.com/fadlypratama/5-billion-project-tentangmu/edit,
diakses tanggal 30 Mei 2014)
Pemilihan lisensi Creative Commons akan menerapkan kesimpulan
lisensi yang dipilih oleh calon pengguna pada keterangan “You’ve
selected the following license: Some Rights Reserved”.
117
4.1.3. Creative Commons Indonesia (CCID)
Creative Commons Internasional (CC HQ) telah memberikan mandat
kepada Ivan Lanin (Wikimedia Indonesia) dan Ari Juliano untuk membentuk,
menerjemahkan, mengharmonisasikan lisensi Creative Commons (CC) dengan
UU Tentang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002. Mulai mengkampanyekan
Lisensi Creative Commons pada tahun 2009, dan telah menerjemahkan Lisensi
Creative Commons kedalam Bahasa Indonesia pada tahun 2011.
Adapun profil singkat dari Diretur dan Wakil Direktur Creative
Commons Indonesia adalah sebagai berikut:
Ari Juliano Gema adalah pimpinan proyek bidang
hukum untuk Karya Cipta Bersama (Creative
Commons) Indonesia. Lahir di Jakarta pada tahun
1976. Merupakan Sarjana Hukum Internasional dari
Universitas Indonesia. Ari memiliki ketertarikan pada
praktek hukum komersial, terutama dalam Hukum
Investasi dan Korporasi, Undang-Undang Telekomunikasi, Teknologi
Informasi, dan Hukum Kekayaan Intelektual. Di luar praktik hukumnya, Ari
memiliki kepedulian dalam subjek Hukum dan Teknologi yang terlihat dari
beberapa tulisannya untuk jurnal dan penyedia media di Jakarta.
Ivan Razela Lanin adalah Pemimpin Proyek
adaptasi lisensi Karya Cipta Bersama atau Creative
Commons Indonesia di tahun 2011. Ivan juga
merupakan salah satu pendiri Perkumpulan
Wikimedia Indonesia di tahun 2008 dan menjabat
Direktur Eksekutif periode 2008-2009 berdasarkan
Resolusi Dewan Pengawas (kini dinamakan Ketua Umum). Ivan aktif sebagai
pembicara dan pelatih dalam seminar dan lokakarya di berbagai daerah tentang
Wikipedia dan lisensi Karya Cipta Bersama (Creative Commons).
118
Creative Commons Indonesia (CCID) diluncurkan bersamaan dengan
Konferensi CC Asia Pasifik pada tahun 2012, bertempat di Grand Sahid Jaya
Hotel, Jakarta pada tangggal 10-11 November 2012.
Gambar 4.5. Logo Creative Commons Indonesia (sumber: http://creativecommons.or.id/, diakses
08 April 2014)
4.1.3.1. Konferensi Creative Commons Asia Pasifik 2012 dan
Peluncuran Creative Commons Indonesia (CCIDAP)
Konferensi Creative Commons Asia Pasifik 2012 dan
Peluncuran Creative Commons Indonesia adalah gabungan acara
pertemuan regional afiliasi Creative Commons di wilayah Asia
Pasifik dan acara peluncuran teks terjemahan lisensi Creative
Commons dalam Bahasa Indonesia. Pertemuan regional ini akan
menjadi media pertemuan afiliasi Creative Commons dari sekitar 15
negara di wilayah Asia Pasifik dan Creative Commons pusat untuk
membahas perkembangan penggunaan lisensi Creative Commons
pada setiap afiliasi. Acara ini juga akan menjadi pertemuan antara
pencipta dan pengguna lisensi Creative Commons di seluruh
Indonesia. Selain itu, salah satu titik berat dari acara ini adalah
sebagai suatu ajang sosialisasi penggunaan lisensi Creative
Commons, dalam bidang pemerintahan, seni dan budaya,
pendidikan, serta ilmu pengetahuan.
Adapun tujuan diadakannya acara ini adalah:
A. Menyebarluaskan teks terjemahan lisensi Creative
Commons versi 3.0 kedalam Bahasa Indonesia;
119
B. Menyosialisasikan penggunaan lisensi Creative
Commons di Indonesia oleh pemerintah, musisi, serta
pada bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan;
C. Memperkenalkan Creative Commons Indonesia kepada
afiliasi Creative Commons dengan secara aktif menjadi
tuan rumah pelaksanaan pertemuan regional Asia Pasifik
yang diadakan setiap dua tahun sekali;
D. Memperkenalkan Indonesia, khususnya Jakarta, kepada
afiliasi Creative Commons.
Gambar 4.6. e-Flyer untuk Konferensi Creative Commons Asia Pasifik 2012 dan Peluncuran
Creative Commons Indonesia (sumber: indonesiannetlabelunion.net, diakses 08 April 2014)
120
Gambar 4.7. Tampilan beranda dari Wikimedia Indonesia tentang Konferensi Creative Commons
Asia Pasifik dan Peluncuran Creative Commons Indonesia (sumber:
http://wikimedia.or.id/wiki/Konferensi_Creative_Commons_Asia_Pasifik_2012_dan_Peluncuran_Creative_Co
mmons_Indonesia/Notulensi_Diskusi_Publik, diakses 08 April 2014)
Pada konferensi tersebut, narasumber yang telah penulis
wawancarai pada kesempatan observasi, Ari Juliano, menjadi
panelis dan berbicara tentang Translating Licenses Into Bahasa
Indonesia (Mengalihbahasakan Lisensi (Creative Commons)
kedalam Bahasa Indonesia). Diskusi tersebut berbentuk forum
terbuka yang berisi Tanya (T) dan Jawab (J) sebagai berikut:
T: Prinsip komersialisasi. Dari sudut pandang media.
Informasi bersifat bebas. Bagaimana pendapatnya dari
sudut pandang media?
J: foto: Foto berbeda dengan informasi lain, kalau tulisan
dengan mudah di quote. Kalau foto ada effort untuk
membuatnya, dia merasa berhak dapat benefit kalau
seandainya foto itu di komersilkan.
T: Freedom of Panorama: kebebasan untuk mengakses karya
yang bernuansa bangunan atau bersifat arsitektur. >>
121
Apakah foto berlatarbelakang arsitektur boleh
diperjualbelikan?
J: Undang-undang hak cipta tidak menyebutkan hal
tersebut, namun ada hak eklsusif. Dengan demikian
kalau mengkomersilkan foto berlatar arsitektur harus
seizin dengan pencipta karya arsitekturnya.
J: Di Indonesia hal ini masih belum jelas. Kembali ke
prinsip awal bahwa tiap individu punya hak ekslusif
untuk memakai foto tersebut. Wikimedia common
menyebutkan foto yang berlatar arsitektur harus seizin
dari pembuatnya.
J: Undang-undang menyebutkan bahwa bangunan yang
tidak diketahui penciptanya maka dinyatakan milik
negara, jika ingin mengkomersilkan arsitektur tersebut
harus izin ke negara. Masalahnya siapa negaranya?
Tidak ada instansi yang jelas atau memiiki hak untuk
menyatakan boleh atau tidak. Sampai sekarang belum
terbentuk instansi yang jelas untuk memberikan
wewenang pemakaian karya-karaya tak bertuan. Oleh
karena itu selalu jadi masalah seandainya ada karya
Indonesia yang tak bertuan dikomersilkan di luar
negeri.
T: Saya (penanya) dapat gambar dari user untuk digunakan
sebagai media komersil, tetapi gambar tersebut dilindungi
oleh salah satu lisensi, sedangkan gambar tersebut akan
dipakai hanya sebatas sebagai souvenir, kalau kasus
seperti ini bagaimana solusinya. Pertanyaan kedua sebatas
apa sih komersil itu?
J: Solusi: Sebagai orang legal, tetap harus berhati-hati
memakai karya orang karena hal tersebut sudah
dikatakan sebagai komersialisasi. Harus ada surat
resmi dari perusahaan yang terkait dengan lisensi
122
gambar tersebut, apabila tidak ada jawaban, sampaikan
pada perusahaan terkait 'apabila dalam 14 hari tidak
ada jawaban maka gambar itu saya pakai', tetapi harus
tetap dicantumkan lisensinya. Katakan kepada
perusahaan tersebut kalau kita sudah melakukan upaya
yang maksimal tapi tidak ada jawaban.
T: Untuk di radio, ada promo program yang menggunakan
musik yang tidak dapat dilihat secara visual
siapa/darimana sumbernya, bagaimana hukumnya?
Kalau sumber Youtube bagaimana? Bagaimana dengan
Soundcloud yang bebas dipakai, apakah boleh diputar di
radio?
J: Radio sudah bekerjasama dengan Yayasan KCI, jadi
masalah tersebut sudah dibayarkan entah di awal
tahun atau di akhir tahun. Youtube bukan pembuat
video, dia hanya memiliki hak siar video. Kalau mau
dikomersilkan harus dengan embed player, jika tidak,
itu akan dikatakan melanggar lisensi Youtube dan hak
cipta si pembuat video. Kalau tidak, cantumkan nama
uploader-nya dan juga link-nya. Tergantung
penciptanya apakah dia membutuhkan benefit kalau
lagunya diputarkan? Kalau radionya online harus
disebutkan dengan jelas link dan sumbernya.
T: Bagaimana dengan foto pahlawan di uang?
J: Seharusnya pihak Bank Indonesia sudah meng-clear-
kan masalah hak cipta foto pahlawan di uang kertas.
T: Bagaimana dengan foto candid jika dikomersilkan?
J: Apakah foto tersebut merugikan orang yang menjadi
objek tersebut? Kalau tidak merugikan tidak apa-apa.
T: Foto Public Element dimodifikasi, jika dipublikasi
bagaimana?
123
J: Prinsipnya apakah orang tersebut niat di foto? Jika ya,
harus izin. Jika candid atau mengalami perubahan,
kembali ke apakah foto tersebut merugikan orang yang
bersangkutan.
T: Dengan diluncurkannya Creative Commons (CC),
bagaimana prosedur penuntutan pelanggaran
hukumnya?
J: Semua kembali ke Undang-Undang Hak Cipta, cukup
datang ke pihak yang berwajib (kepolisian) apabila
menemukan atau menjadi korban pelanggaran hak
cipta. CC hanya sebatas status karya, apa yang boleh
dan tidak boleh dilakukan oleh orang lain (diluar
pencipta), tetapi segala sesuatunya akan dikembalikan
ke undang-undang dan pengadilan.
T: Istilah-istilah di web agak sedikit membingungkan,
karena penyerapan dari Bahasa Inggris ke Bahasa
Indonesia sulit untuk dipahami
J: Masalah bahasa tidak ada masalah, karena di dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa tersebut baik
dan benar serta tepat untuk menjelaskan arti dari
Bahasa Inggris, masalahnya istilah-sitilah tersebut
masih belum disosialisasikan, jadi masih sulit atau
kebingungan ketika berhadapan dengan istilah-istilah
tersebut. Mungkin solusinya akan dibuatkan glossary
(perbendaharaan kata) mengenai istilah-istilah
tersebut.
T: Apakah CC satu-satunya organisasi?
J: CC itu organisasi terbuka, CC sendiri dikhususkan
karya-karya digital yang non software (seni, sastra dan
ilmu pengetahuan). CC sudah direkomenadasikan oleh
UNESCO karena dianggap paling mudah untuk
dipahami.
124
T: Di kampus ada seni musik dan seni tari, pada setiap
semesternya ada pentas seni yang di aransemen, dan
pentas tersebut ingin di publikasikan ke media, bagaimana
lisensinya?
J: Jika publikasi video dan di Youtube, masalah hukum
di Youtube sudah jelas, jika memang akan
menggunakan lisensi CC juga bisa.
Ari Juliano: Masih banyak PR (pekerjaan rumah) mengenai undang-
undang hak cipta, terutama di Indonesia, hukumnya masih
belum jelas, institusi yang berwenang pun tidak ada, hal-
hal yang dibahas masih hal-hal yang umum, belum ada
pembatasan-pembatasan yang pasti, seperti halnya di
Amerika pada contoh kasus fotocopy buku pelajaran.
Disana ada lembaga yang mengatur jika fotocopy buku
hanya boleh 5 lembar, jika lebih harus bayar royalti, di
Indonesia belum bisa berfikir sejauh itu.
Dalam Konferensi CC Asia Pasifik 2012 dan Peluncuran
CCID tersebut, Ivan Lanin (Wikimedia Indonesia) juga
berkesempatan menjadi panelis dalam sebuah dialog dengan para
peserta konferensi dalam diskusi publik, dan menghasilkan
notulensi yang menjelaskan beberapa poin penjelasan mengenai CC
untuk pemula. Antara lain sebagai berikut:
1. Summary of presentation
Lisensi CC adalah lisensi hak cipta yang
menjembatani kepentingan pencipta dan kebebasan
pengguna terhadap ciptaan/karya.
Hak cipta adalah hak eksklusif untuk mengumumkan
atau memperbanyak suatu ciptaan yang timbul secara
otomatis tanpa mengurangi pembatasan.
125
Hak cipta terdiri dari hak moral (hak yang menyatakan
bahwa suatu karya adalah ciptaan pencipta itu sendiri,
(contoh: tulisan di blog, hak moralnya ada di
penulisnya) dan hak ekonomi (berkaitan dengan unsur
“memperbanyak” didalam pengertian hak cipta).
Pengertian “otomatis” dalam hak cipta, adalah ketika
suatu karya diciptakan, hak cipta sudah lahir, tanpa
harus didaftarkan. Namun, permasalahan mengapa
harus didaftarkan adalah untuk kepentingan
pembuktian.
CC bukan membentuk Undang-undang baru, tapi
hanya memberikan sebuah sarana eksplisit bagi hak
cipta untuk membantu pembuktian.
2. Mengapa harus dilindungi?
Pencipta: mempertahankan hak moral dan ekonomi
terhadap ciptaan sambil mendorong penyebaran dan
penggunaan ciptaan.
Pengguna: mengetahui secara persis apa yang dapat
dilakukan terhadap suatu ciptaan.
Umum: meningkatkan penghargaan terhadap hak
cipta dan mendorong penciptaan baru. Karya di
Indonesia, hak cipta belum terlalu diperhatikan.
(Contoh: pengambilan gambar dari internet secara
bebas, tanpa mencantumkan nama penciptanya).
3. Komponen Penting Creative Commons
126
Syarat: bagian dimana kita menentukan hak mana
yang kita lepas, atribusi, non komersial (harus
meminta izin), tanpa turunan (hanya karya asli yang
digunakan dan tidak diturunkan ke karya lain) atau
berbagi serupa.
Lisensi, yang disediakan oleh CC sendiri, yakni BY;
BY-SA; BY-NC; BY-ND ; BY-NC-SA; dan BY-BC-
ND. Lisensi-lisensi ini dilambangkan oleh CC dengan
penggunaan logo-logo, yang ditujukan agar mudah
dipahami oleh masyarakat luas.
Format, yakni ringkas (deed) untuk kaum awam,
lengkap (legal) untuk pihak konsultan hukum, dan
digital (digital) untuk metadata yang dipahami mesin
pencari, seperti di dalam advanced search pada mesin
pencari Google.
4. Dimana CC dapat digunakan?
Media yang dapat menggunakan lisensi CC (tulisan,
audio/musik, foto/gambar, video)
Bidang yang dapat menggunakan lisensi CC
(kebudayaan pendidikan, pengetahuan seperti akses
terhadap jurnal-jurnal penelitian, pemerintahan
(contoh: di pemerintahan Australia, dimana semua
produk pemerintahannya telah berlisensi CC).
45
5. Contoh-contoh pihak yang telah menggunakan CC
Wikipedia
Al-Jazeera
Deviantart
Bottlesmoker
Indonesian
Netlabel Union
Beberapa video di
YouTube
PloS (sumber jurnal)
MIT Opencourseware
White House, dan
Pemerintah Australia.
6. Komunitas Webseries Indonesia
Medium online video yang tayang perdana di internet
secara berseri atau rutin, karya-karya yang ada disini
adalah sepenuhnya karya asli Indonesia, media
semacam ini dimulai sekitar tahun 2007-2008, namun
komunitas ini sendiri mulai aktif di awal 2012.
Lahirnya komunitas ini adalah atas kecintaan para
pendiri komunitas ini dengan film dan TV. Karya-
karya disini meliputi berbagai macam karya, baik
karya video fiksi, non-fiksi, musik, dan lain-lain.
Di Indonesia, antusias atas video online ini tinggi,
namun permasalahan yang timbul disini adalah
komunitas indie yang merasa media ini sangat efektif,
namun mereka merasa karyanya tidak terlindungi,
khususnya atas pembajakan karya. Karena itulah
komunitas ini merasa perlu lisensi CC digunakan di
web mereka, agar perlindungan atas karya mereka
lebih pasti.
79
7. Forum terbuka (Tanya (T) & Jawab (J))
T: Bagaimana penggunaan CC pada foto dalam blog?
Apakah butuh setiap foto di watermark dengan logo
CC?
J: Dapat diberikan watermark, tapi hal itu tidak perlu,
karena sejatinya apabila di dalam blog itu telah
dilindungi dengan lisensi CC, maka perlindungan
terhadap seluruh blog itu telah terjamin oleh CC.
T: Bagaimana dengan perlindungan atas CC karya fisik
seperti buku/CD?
J: Dimasukkan logo CC di karya fisik tersebut.
T: Bagaimana dengan perlindungan atas CC karya
video?
J: Biasanya dimasukkan logo CC ke credits.
T: Bagaimana perlindungan lisensi CC atas lagu?
J: Dalam pelekatan pada karya audio, lisensi CC
dengan media audio (yang berbentuk gelombang
suara) mempunyai banyak kendala. Jadi yang
dapat dilakukan adalah mencantumkan lisensi CC
itu pada bungkus CDnya, atau dicantumkan
lisensinya di web dimana lagu itu dibagikan. Perlu
diingat lagi bahwa CC ini ada untuk perlindungan
awal. Perlindungan CC ini sendiri juga dibutuhkan
oleh pencipta dan pengguna, untuk menyatakan
bahwa mereka “satu pihak” dalam hal ini, yakni
mendukung penegakan hak cipta.
80
Dalam acara Konferensi Creative Commons Asia Pasifik 2012
dan Peluncuran Creative Commons Indonesia ini juga, CCID
mengeluarkan desain poster yang berisikan informasi penting dan
umum mengenai Creative Commons, Creative Commons Indonesia
dan bentuk-bentuk lisensi yang dikeluarkan Creative Commons
Internasional (CCHQ) kemudian diterjemahkan kedalam Bahasa
Indonesia. Berikut ini adalah tampilan dari poster keluaran Creative
Commons Indonesia yang dimaksud:
81
Gambar 4.8. Poster kampanye CCID berisikan lisensi Creative Commons (sumber:
http://creativecommons.or.id/hubungi-kami/) (diakses 09 April 2014)
82
4.1.3.2. Indonesian Netaudio Festival 1
Dalam masa kampanyenya, CCID juga tengah bekerja sama
dengan Indonesian Netlabel Union (INU), membuat festival audio
pertama dengan konten acara mempertemukan beberapa pengguna
lisensi CC, artis dan pengguna internet yang mengkonsumsi karya-
karya yang berlisensikan CC. Pada kesehariannya individu-individu
tersebut hanya berkomunikasi dan bercengkrama melalui media internet
(tidak bertemu langsung di lapangan). Festival audio ini bertemakan
Indonesian Netaudio Festival 1 (INF#1), yang diselenggarakan pada
tanggal 16-17 November 2012 di Yogyakarta.
Gambar 4.9. Pamflet dan e-Flyer dari INF 1 (sumber:
http://indonesiannetlabelunion.net/indonesian-netaudio-festival-1/, diakses 09 April 2014)
Tidak haya dihadiri oleh konsumen audio yang didistribusikan
melalui media internet saja, INF#1 juga dihadiri beberapa perwakilan
netlabel-netlabel seluruh Indonesia. Beberapa perwakilan tersebut
yakni:
Yes No Wave Music,
Inmyroom Records,
Hujan! Rekords,
StoneAge Records,
MindBlasting,
Pati Rasa Records,
Tsefula/Tsefuelha
Records,
KANAL 30,
EarAlert Records,
Lemari Kota,
Experia,
84
4.1.3.3. Interview dengan Anggung Kuy Kay
Pada kesempatan observasi yang dilakukan penulis dengan
salah satu peserta INF#1 dan juga artis yang aktif dalam pergerakan dan
pendistribusian karya melalui media internet yakni sdr. Anggung Kuy
Kay (Angkuy) dari Bottlesmoker, penulis mendapatkan data dalam
wawancara singkat yang dilakukan secara privat pada kantor dari band
Bottlesmoker di Jalan Ir. H. Juanda nomor 500 (Dago500), Bandung,
Jawa Barat.
Berikut hasil dari wawancara tersebut. Penulis tuangkan dalam
bentuk Tanya (T) dan Jawab (J).
T: Sejauh mana Bottlesmoker terkait dengan pemasaran karya musik di
Internet?
J: Bentuk pendistribusian karya-karya musik Bottlesmoker dalam
pemasarannya memang sangat menggunakan media internet
sebagai media distribusi karya itu sendiri. Dikarenakan memang
semenjak awal, Bottlesmoker menggunakan media komputer
sebagai penyebar karya. Dalam hal ini, Bottlesmoker pernah
“menitipkan” karya musik dari Bottlesmoker kepada komputer
server pada beberapa Warung Internet (warnet), dengan maksud
agar dapat diakses (dikopi, didengar: dikonsumsi, pen) oleh
pengguna warnet yang kebetulan membutuhkan musik pada saat
mengakses internet di warnet tersebut.
T: Bagaimana keikutsertaan Bottlesmoker dalam penerapan dan
kampanye lisensi Creative Commons di Indonesia?
J: Bottlesmoker menggunakan lisensi Creative Commons sejak
tahun 2008, dan telah merilis karya musik secara “bebas”
melalui internet sejak 2006. Dalam lisensi di internet itu sendiri,
Bottlesmoker memilih menggunakan lisensi dengan bentuk
85
“Copyleft” (pada freeware – perangkat lunak bebas) atau CC
BY-SA (Atribusi-BerbagiSerupa) pada lisensi Creative
Commons.
T: Mengapa Bottlesmoker memilih membagikan karya musik
Bottlesmoker secara “bebas” di internet?
J: Pertama: Bottlesmoker memang salah satu penggiat, pengguna
sekaligus penikmat piranti lunak “bebas” yang pada hari ini
sudah sangat banyak dibagikan dan dengan mudah diakses lewat
internet. Baik penggunaannya pada telepon genggam pintar
(Smartphone), maupun pada personal computer (PC). Jadi
Bottlesmoker memang menginginkan penikmat musik
Bottlesmoker mengonsumsi karya Bottlesmoker secara bebas,
sama halnya dengan penggunaan piranti lunak bebas (freeware)
tersebut.
Kedua: Bottlesmoker tidak mengharapkan materi berbentuk
pembelian dengan uang dari masing-masing karya yang telah
Bottlesmoker ciptakan dan distribusikan diinternet secara bebas.
Akan tetapi Bottlesmoker lebih menekankan aspek pemasaran
karya musik Bottlesmoker pada Merchandise dan Live
Performance. Disisi lain Bottlesmoker juga “menjual” karya
musik dalam bentuk fisik (Audio-CD) dengan kemasan
(packaging) yang menarik, untuk keperluan pengguna yang
ingin mengoleksi karya musik Bottlesmoker dalam bentuk fisik.
CCID juga telah membuat sebuah diskusi sosial tentang
pemahaman hak cipta di beberapa kota besar Indonesia, bekerja sama
dengan sebuah lembaga belajar yang bernama Akademi Berbagi
(Akber). Akber tersebut telah tersebar di seluruh Indonesia dan telah
memiliki tenaga pengajar sebanyak orang. Berikut data berbentuk
pamflet/e-flyer dari acara yang telah dilaksanakan oleh Creative
Commons dan Akber:
86
Gambar 4.10. Pamflet/e-Flyer dari acara diskusi oleh Creative Commons bekerja sama
dengan Akademi Berbagi (sumber: https://www.facebook.com/CreativeCommonsIndonesia,
diakses 17 April 2014)
87
4.2. PEMBAHASAN
Pada sub-bab ini, penulis akan memaparkan dan mulai mengsinkronisasikan
data yang penulis dapatkan selama observasi yang telah penulis lakukan
sebelumnya, dengan pendapat para pakar yang telah penulis kaji dari studi literatur.
Seperti yang dikatakan oleh Cresswell (2007: 55 (4)) dalam langkah-langkah
melaksanakan penelitian naratif, salah satunya ialah
menganalisa cerita partisipan dan kemudian menceritakan ulang (restory)
cerita mereka ke dalam kerangka kerja yang masuk akal. Restorying adalah
proses organisasi ulang cerita ke dalam beberapa tipe umum kerangka kerja.
Kerangka kerja ini meliputi pengumpulan informasi, penganalisaan
informasi untuk elemen kunci cerita (misalnya: waktu, tempat, alur, dan
scene/adegan) dan menulis ulang cerita guna menempatkan mereka dalam
rangkaian secara kronologis.
Dari keterangan diatas, penulis telah menganalisa beberapa fenomena selama
masa observasi dan mendapatkan beberapa pokok permasalahan yang dapat penulis
uraikan sebagai berikut:
4.2.1. Pelaku Berbagi-File
Dalam Lessig (2004), terdapat tipe-tipe pelaku berbagi-file.
A. Sebagian orang menggunakan jejaring berbagi ini sebagai
pengganti dari membeli konten. Jadi, ketika CD terbaru Madonna
diluncurkan; dari pada membeli, pengguna dengan mudah dapat
mengambilnya. Kita mungkin bisa berangan-angan apakah setiap
orang yang mengambil konten, benar-benar akan membelinya jika
jaringan ini tidak menyediakannya secara gratis. Sebagian besar
mungkin tidak akan melakukannya, tapi jelas, ada beberapa yang
bersedia membeli. Yang belakangan ini adalah sasaran dari
kategori A: yaitu pengguna yang mengunduh ketimbang membeli.
B. Sebagian pengguna menggunakan jejaring berbagi ini untuk
menyicipi karya musik tertentu sebelum membelinya. Jadi
misalnya, seorang teman mengirimkan teman yang lain sebuah
file MP3 dari seorang artis yang belum pernah ia dengar
88
sebelumnya. Kemudian teman yang lain itu membeli CD artis
tersebut. Ini merupakan salah satu jenis iklan yang punya sasaran
khusus, dan biasanya cukup berhasil. Jika seorang teman tidak
mendapatkan apa pun karena rekomendasinya yang buruk, ia bisa
saja berharap bahwa rekomendasi tersebut sebenarnya cukup
baik. Efek jejaring dari kegiatan berbagi dapat meningkatkan
jumlah musik yang diperjualbelikan.
C. Ada banyak pengguna yang menggunakan jaringan berbagi ini
untuk mendapatkan akses konten berhak cipta yang sudah tidak
lagi dijual atau bahwa mereka tidak dapat membelinya karena
biaya transaksi di luar Internet sangatlah tinggi. Penggunaan
jaringan berbagi seperti merupakan salah satu bentuk yang paling
menguntungkan bagi banyak orang. Lagu-lagu yang pernah
menjadi bagian dari masa kecil anda dan sudah lama menghilang
dari pasar, secara ajaib muncul lagi di dalam jejaring ini.
(Seorang teman mengatakan kepada saya bahwa ketika ia
menemukan Napster, ia menghabiskan sepanjang akhir pekannya
untuk “bernostalgia” dengan lagu-lagu lama itu. Ia dikejutkan
dengan ragam dan bauran konten yang tersedia di sana). Untuk
konten yang tidak dijual, secara teknis aktivitas ini jelas
merupakan pelanggaran hak cipta, meskipun nilai kerugian
ekonomisnya hanya nol karena pemilik hak cipta tidak lagi
menjual kontennya. Kerugian yang sama juga terjadi ketika saya
menjual koleksi piringan hitam 45-rpm tahun 1960an saya kepada
kolektor lokal.
D. Terakhir, ada banyak orang yang menggunakan jaringan berbagi
untuk mendapatkan akses ke materi yang tidak berhak cipta atau
pemilik hak ciptanya ingin memberikannya secara gratis.
89
Lessig (2004) menyebutnya sebagai “para pelaku berbagi-file
membagi-bagikan berbagai macam konten. Kita dapat membedakannya ke
dalam empat tipe”. Kemudian pada point “D” dapat dilihat bahwa ada
pengguna internet yang menggunakan jaringan berbagi untuk mendapatkan
akses ke materi yang tidak berhak cipta atau “pemilik hak ciptanya ingin
memberikannya secara gratis”.
Pernyataan Lessig (2004) tersebut bisa dihubungkan dengan beberapa
perlakuan lisensi keluaran Creative Commons yang “membebaskan” pemilik
hak cipta serta pengguna karya dalam pola konsumsi karya musik digital yang
diciptakan oleh si pencipta/artis. Hal tersebut dikarenakan dalam poin-poin
Lisensi Creative Commons (Bab II, sub-bab 2.2.), terdapat bentuk lisensi yang
berbunyi:
lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki
dan membuat ciptaan turunan, bahkan untuk kepentingan
komersial, selama mereka (pengguna karya) mencantumkan kredit
kepada Pemilik Ciptaan atas ciptaan asli. Seluruh ciptaan turunan
dari ciptaan si Pemilik Ciptaan akan memiliki lisensi yang sama,
sehingga setiap ciptaan turunan dapat digunakan untuk kepentingan
komersial. Lisensi ini digunakan oleh Wikipedia dan
direkomendasikan untuk materi-materi yang berasal dari
penghimpunan materi Wikipedia dan proyek dengan lisensi serupa
(Lisensi Atribusi CC BY-SA).
Pada penerapannya di industri perangkat lunak bebas (freeware),
terdapat juga lisensi yang dikenal sebagai “copyleft” (akan penulis bahas pada
sub-bab selanjutnya). Lisensi tersebut membebaskan pencipta dalam
menyebarkan karyanya pada media apapun, baik pada media situs web
maupun pada media CD fisik kepada pengguna karyanya, yang selanjutnya si
pengguna karya dapat dengan bebas menggubah, mengadaptasi, me-remix,
bahkan menggunakannya untuk kepentingan komersial, selama konsumen
yang akan mengadaptasi menyebutkan bahwa karya yang diciptakan tersebut
90
mempunyai Pemilik yang memegang Hak Ciptanya secara penuh. Jadi
konsumen tersebut harus selalu menyebutkan pencipta asli dari karya tersebut
dalam credit title pada setiap pengaplikasian karya yang dibuat oleh
konsumen tersebut. Hal tersebut dikarenakan memang pada dasarnya bentuk
freeware itu sendiri memang sangat dinikmati oleh para pemakai telepon
pintar (smartphone) yang pada saat ini sedang marak-maraknya.
Para pengguna freeware tersebut terkadang kurang menyadari bahwa
yang sedang mereka konsumsi saat itu adalah bentuk dari freeware yang
memang dibuat khusus oleh para penciptanya, agar konsumen terinspirasi,
terhibur dan bahkan termudahkan oleh freeware yang telah si pencipta buat.
Seperti contohnya salah satu freeware Soundcloud. Freeware tersebut
memudahkan para pencipta karya dalam mempromosikan karya-karya
musiknya di internet. Soundcloud dalam beberapa syarat dan ketentuannya,
memudahkan pengguna internet dalam mengakses karya-karya musik
unggahan para pencipta musik. Tetapi Soundcloud pun menyadari dan
memberikan perhatian terhadap pembajakan yang memang sudah sangat biasa
pada era informasi seperti sekarang ini. Jadi, Soundcloud menyertakan
pertanyaan, sebelum pengunggah mengunggah karyanya ke internet.
Pertanyaan tersebut berbentuk kolom yang harus dipilih oleh para
pengunggah karya musik, apakah pengunggah tersebut memilih karya
musiknya dilindungi oleh hak cipta biasa atau oleh lisensi Creative Commons.
Berikut tampilan kolom pilihan tersebut:
91
Gambar 4.11. Pemilihan Lisensi pada Pengunggahan karya di Soundcloud (sumber:
http://soundcloud.com/(pengguna/pengunggah)/(judul-karya)/edit, diakses 09 Mei 2014)
Pola penyebaran berasaskan lisensi seperti diatas telah dibenarkan
pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta, dalam pasal 1 poin 14, yang berbunyi:
Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau
Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan
dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya
dengan persyaratan tertentu.
Kemudian tentang bagaimana dengan proses penindakan yang
dilakukan oleh pihak berwajib, jika terdapat pelanggaran-pelanggaran pada
praktek setelah diterapkannya lisensi tersebut pada sebuah karya? Pertanyaan
tersebut dapat dilihat pada pendapat Ari Juliano (CCID) yang menjadi panelis
di Konferensi Creative Commons Asia Pasifik 2012 dan Peluncuran Creative
Commons Indonesia, yang telah dibahas pada sub-bab sebelumnya.
Pernyataan tersebut berbunyi:
92
Semua kembali ke Undang-Undang Hak Cipta. Pencipta cukup
mendatangi pihak yang berwajib seperti kepolisian apabila
menemukan atau menjadi korban pelanggaran Hak Cipta. Creative
Commons hanya sebatas status karya tentang “apa yang boleh dan
tidak boleh dilakukan orang lain (konsumen, pengguna karya – diluar
pencipta asli)”. Tetapi segala sesuatunya akan dikembalikan lagi ke
undang-undang dan pengadilan.
Ari Juliano juga berpendapat pada kesempatan observasi langusng
yang dilakukan oleh penulis.
Lisensi Creative Commons seperti status pada media sosial Facebook.
Pada Facebook, kita bisa melihat beberapa status; Single, In
Relationship (dalam hubungan), Engaged (bertunangan), Married
(menikah), It’s Complicated (bermasalah), dan sebagainya.
Lisensi ini pun sama. Jadi secara sosial, publik lain (diluar pemilik
akun Facebook) akan merasa terbatasi oleh status tertentu yang
dipajang oleh si pemilik akun tersebut. Apa yang bisa dan tidak bisa
dilakukan oleh Pengguna Facebook lain terhadap si pemilik akun
tersebut. Relasi semacam apa yang memungkinkan untuk dilakukan
pengguna Facebook lain kepada si pemilik akun, jika si pemilik akun
telah memasang status Married (Menikah). Ada hukum sosial yang
berbicara jika terdapat pelanggaran oleh si pengguna facebook lain
kepada si pemilik akun, atau sebaliknya.
4.2.2. Visi Publik
Terciptanya Creative Commons ternyata tidak menghentikan
persaingan diantara dua kubu publik yang memiliki visi bertentangan. Kim
(2005: 188), ada dua visi bersaing dari dasar-dasar hukum hak cipta: yakni “visi
milik pribadi – private property” dan “visi kebijakan publik – public policy
vision”.
93
A. Visi milik pribadi tercetus karena adanya kelompok yang
mendukung dan percaya bahwa hak cipta berasal dari alam sebagai
hak milik penulis (pencipta), dan bahwa penulis yang membuat
karya asli berhak untuk memiliki hak milik atas pekerjaan mereka.
Penekanan visi milik pribadi adalah pada kepentingan pribadi si
penulis (pencipta) dalam mengendalikan penggunaan karya cipta
sebagai milik si penulis (pencipta). Bertentangan dengan,
B. Visi kebijakan publik. Diadakan oleh mereka yang mencatat hak
cipta yang secara historis berkembang sebagai hibah didalam
masyarakat dari monopoli terbatas, dan yang berpikir bahwa hak-
hak pencipta harus mempertimbangkan kebebasan orang lain untuk
menggunakan karya berhak cipta. Visi ini disebut visi kebijakan
publik karena menggarisbawahi pentingnya kepentingan publik
dalam mengakses dan menggunakan karya berhak cipta. Hal ini
juga menggarisbawahi peran hak cipta sebagai suatu kebijakan
publik yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan yang tepat
antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum.
Menurut Kim (2005), kedua visi tersebut telah bentrok dalam
perkembangan hukum hak cipta selama 300 tahun. Akan tetapi konflik yang
terjadi diantara kedua kubu tersebut lebih meningkat di era digital ini. Secara
otomatis pihak advokasi dari kedua visi tersebut mempunyai cara pandang yang
berbeda terhadap peningkatan teknologi digital. Bagi advokat dari visi milik
pribadi berharap, dengan lebih berkembangnya teknologi digital akan
meningkatkan pengumpulan “biaya” pada setiap penggunaan hak cipta karya-
karya mereka (Goldstein: 2003). Tetapi yang terjadi pada pengamatan mereka
adalah pelanggaran hak cipta besar-besaran, yang membuat pelembagaan
mekanisme pada industri musik putus asa dalam melakukan penegakan yang
kuat terhadap “penyalinan”, dalam rangka melindungi kepemilikan mereka.
Dari sudut pandang penulis, visi milik pribadi tersebut seperti selalu
ingin mendahulukan kepuasan dari segi hak ekonomi yang mereka tuntut dari
94
setiap karya yang mereka ciptakan. Hal tersebut sesungguhnya bertentangan
dengan fenomena yang terjadi pada masyarakat dengan tingkat perkembangan
teknologi seperti sekarang ini. Jadi menurut sudut pandang penulis, para
penganut faham visi milik pribadi tersebut seharusnya agak membuka diri
terhadap perkembangan teknologi, bahwa pola penyebaran dan pendistribusian
di industri musik hari ini tidak selalu berbicara soal “membayar” karya dengan
materi atau uang.
Pada pertemuan keempat antara penulis dengan dosen pembimbing
dalam masa bimbingan, penulis mendapatkan fenomena yang dikemukakan
oleh dosen pembimbing penulis yakni Ahmad Hidayat, beliau menyatakan;
“industri musik pada saat ini telah menginjak kepada masa dimana publik lebih
memilih untuk menjadi sosialis dibanding menjadi kapitalis”. Dengan maksud
bahwa publik didalam industri musik pada hari ini telah sadar, bahwa
pemasaran sebuah karya musik dapat dimulai dengan memberikan secara cuma-
cuma karya yang diciptakan oleh pencipta musik kepada konsumen karya
musik, tetapi dengan catatan bahwa pencipta tersebut harus sadar akan hak
moral dan hak ekonomi dari pemasaran karya musik jenis ini.
4.2.2.1. Hak Moral dan Hak Ekonomi
Menurut data yang penulis dapatkan pada saat observasi,
Angkuy Bottlesmoker mengemukakan, pernah pada satu kesempatan,
beliau yang berada dipihak visi kebijakan publik, bertemu dan
berdiskusi di sebuah forum dengan Mas Piyu yang pada kesempatan
tersebut berada dipihak visi milik pribadi. Mas Piyu bertanya kepada
Angkuy, mengapa pada setiap karya yang Angkuy buat, Angkuy lebih
memilih untuk menyebarkannya secara “gratis”? Sedangkan yang
dirasakan oleh Mas Piyu pada saat itu adalah merosotnya angka
penjualan CD Audio yang dihasilkan oleh bandnya. Angkuy menjawab
dengan pengetahuannya tentang Lisensi Bebas ala Creative Commons.
Yang kita lihat disini adalah bukan semata-mata melihat nilai
nyata pada hasil penjualan karya yang berbentuk fisik,
melainkan adanya perasaan “menyenangkan” ketika publik
95
(common) membuat status pada sosial media miliknya yang
menyebutkan, bahwa dirinya sedang memainkan
(mendengarkan) karya dari Bottlesmoker. Fenomena tersebut
dikenal sebagai Now Playing.
Kemudian timbulnya semangat baru ketika ada negara afiliasi
Creative Commons (negara yang telah mempunyai lembaga
mapan yang sudah menggunakan lisensi Creative Commons)
lain yang mengundang Bottlesmoker untuk bermain (perform)
di salah satu acara pameran seni di negara mereka. Seperti
Thailand, Vietnam, Malaysia dan Brunei Darussalam.
Now Playing tersebut terjadi ketika seseorang memainkan
sebuah karya milik orang lain, kemudian orang tersebut memasangnnya
(posting) pada status di sosial media milik orang tersebut. Hal ini
menimbulkan dua pemikiran, yakni; bahwa orang tersebut memiliki
“salinan asli” dari karya yang ia “beli dengan uang” kemudian ia
posting, sementara ia memainkannya pada sebuah pemutar musik
miliknya, atau orang tersebut memiliki “salinan digital asli” yang ia
dapatkan dari pengunduhan (downloading) yang ia lakukan pada salah
satu situs web resmi dari sebuah pencipta karya musik (band, pen), lalu
mem-posting-nya sebagai status.
Ada pula perlakuan menyenangkan lain dari pihak konsumen
Bottlesmoker, yang pernah pada suatu saat dibelakang sebuah
panggung Bottlesmoker di Indonesia. Bottlesmoker dihadiahi
instrumen musik berbentuk keyboard dari pendengar setia
Bottlesmoker yang merasa puas dan terhibur oleh musik
Bottlesmoker yang memang pada saat itu, konsumen tersebut
mengaku telah mengunduh secara “bebas” melalui situs resmi
Bottlesmoker.
Berdasarkan data diatas, bahwa hak moral yang didapatkan
oleh Bottlesmoker adalah perasaan menyenangkan ketika ada konsumen
karyanya yang kedapatan memainkan atau mendengarkan karya dari
Bottlesmoker lalu di-posting oleh konsumen tersebut sebagai status
96
pada media sosial milik si konsumen (Now Playing). Sedangkan hak
ekonomi yang Bottlesmoker dapatkan adalah dengan diundangnya
Bottlesmoker ke festival-festival yang diselenggarakan oleh negara
afiliasi CC lain yang telah merilis karya Bottlesmoker dibawah naungan
Netlabel di negara mereka, kemudian Bottlesmoker mendapatkan
bayaran yang setimpal bahkan berlebih dalam biaya administratif. Hak
ekonomi lain yang dirasakan Bottlesomker yakni dari instrumen musik
yang didapatkan secara cuma-cuma dari konsumen, yang ingin
berterimakasih kepada Bottlesmoker, karena telah membuat karya yang
indah, serta menyebarkannya secara cuma-cuma, tanpa harus membayar
sepeser pun.
Akan tetapi, setelah penulis melakukan konseling lebih lanjut
mengenai hak moral dan hak ekonomi ini, penulis menemukan bahwa
teori hak moral belum terpenuhi, ketika sebuah karya musik diakui oleh
publik hanya dengan fenomena Now Playing. Hal ini terdapat pada
Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 yang bebunyi:
Bagian Ketujuh
Hak Moral
Pasal 24
(1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang
Hak Cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan
dalam Ciptaannya.
(2) Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya
telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan
persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli
warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku
juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan,
pencantuman dan perubahan nama atau nama samara
Pencipta.
97
Adapun keterangan lebih lanjut mengenai informasi
elektronik, terdapat juga pada bagian pasal Hak Moral yang sama,
berbunyi:
Pasal 25
(1) Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak
Pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah.
Selanjutnya pada Pasal 5 Ayat (1), disebutkan tentang
Pencipta, bahwa:
Bagian Kedua
Pencipta
Pasal 5
(1) Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai
Pencipta adalah:
a. orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum
Ciptaan pada Direktorat Jenderal; atau
b. orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau
diumumkan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan.
Kemudian pada Pasal 6, disebutkan:
Pasal 6
Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri
yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap
sebagai Pencipta ialah orang yang memimpin serta
mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan itu, atau dalam hal
tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai Pencipta
adalah orang yang menghimpunnya dangen tidak mengurangi
Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya itu.
98
Dengan demikian, hak moral baru bisa dikatakan terpenuhi
jika karya musik yang telah dirilis ke publik oleh si pencipta dalam
kondisi telah terdaftarkan di Ditjen HKI dan karya musik tersebut sudah
jelas pengarangnya, kemudian publik dan/atau media lain diluar si
pencipta, merespon karya tersebut dengan perlakuan “selalu
mengatribusi” atau “selalu menyertakan nama si pencipta” jika karya
musik tersebut telah berubah bentuk, atau berpindah tempat dan media,
atau digunakan oleh pihak lain dalam bentuk adaptasi karya.
Contohnya, jika karya musik Bottlesmoker akan digunakan
sebagai soundtrack sebuah iklan layanan masyarakat, maka si pembuat
iklan layanan masyarakat tersebut haruslah menyertakan nama pencipta
didalam kredit iklan layanan masyarakat tersebut. Contoh lainnya, jika
karya musik Bottlesmoker telah dijadikan video clip, kemudian video
clip tersebut akan ditayangkan pada salah satu stasiun televisi, maka
stasiun televisi tersebut harus menuliskan nama pencipta karya musik
tersebut, disela-sela penayangan video clip tersebut. Barulah hak moral
yang dimaksudkan undang-undang hak cipta tersebut terpenuhi.
Kemudian sesungguhnya Bottlesmoker belum termasuk
kategori yang terpenuhi hak ekonominya, jika hanya diundang oleh
negara afiliasi CC lain dan mendapatkan instrumen musik dari publik
yang berterimakasih atas karya yang telah Bottlesmoker ciptakan.
Fenomena tersebut hanya merupakan “dampak ekonomi” dan belum
termasuk kedalam kategori “hak ekonomi”.
Akan tetapi penulis menemukan fenomena tentang “hak
ekonomi” lain yakni, berhasil dijualnya beberapa rilisan fisik dari karya
musik Bottlesmoker kepada konsumen yang sebelumnya telah
mengenal Bottlesmoker dan telah mendengar karya Bottlesmoker
melalui hasil unduhan karya musik Bottlesmoker yang telah disebarkan
di situs resmi Bottlesmoker. Menurut pengakuan konsumen tersebut
kepada Bottlesmoker, bahwa karya Bottlesmoker tersebut dianggap
baik. Maka mereka ingin memiliki rilisan fisik dengan packaging
(kemasan CD, pen) ala Bottlesmoker, serta beberapa informasi lain yang
99
tidak didapatkan pada rilisan digital di situs resmi Bottlesmoker.
Konsumen seperti ini dapat dimasukkan ke dalam kategori B pada
pelaku berbagi-file menurut Lessig (2004) yang “menggunakan
jaringan berbagi tersebut untuk “menyicipi” karya musik tertentu
sebelum membelinya.”
Memasuki pembahasan sisi negatif dari penyebaran karya
melalui media internet secara bebas. Dalam hal ini, penulis juga
mendapatkan data dari Angkuy yang telah menyebarkan karya musik
Bottlesmoker secara bebas di internet. Angkuy meyatakan bahwa
pernah suatu ketika ada konsumen karya Bottlesmoker yang
menggunakan karya Bottlesmoker sebagai musik pengiring
sebuah iklan komersial di televisi. Konsumen tersebut
sepertinya asal pakai dan tidak tahu bahwa karya tersebut
sebetulnya telah di lisensikan dengan Lisensi CC BY-NC-SA
atau Lisensi yang mengizinkan setiap orang untuk
menggubah, memperbaiki dan membuat ciptaan turunan
bukan untuk kepentingan komersial, selama mereka
mencantumkan kredit kepada pencipta dan melisensikan
ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan
asli. Tetapi pada saat itu Saya tidak mengusutnya secara
hukum yang berlaku. Jadi sampai saat ini belum ada
penyelesaian.
Padahal, jika dibandingkan dengan kasus yang terjadi pada
Else dan Fox pada Lessig (2004: 113):
Jon Else sedang membuat film dokumenter berjudul Ring
Cycle (The Ring) karya Wagner. Fokus dari film ini ialah para
kru panggung di gedung opera San Francisco. Kru panggung
adalah elemen khusus yang lucu dan berwarna dalam sebuah
opera. Ketika opera berlangsung, mereka biasa duduk-duduk
di bawah panggung atau di ruang operator lampu.
Suatu ketika, dalam sebuah pertunjukan, Else merekam
beberapa kru panggung sedang bermain dam-daman. Di
100
pojok ruangan terdapat satu televisi. Kala itu, ketika para kru
panggung bermain dam dan opera sedang memainkan
Wagner, televisi sedang menyiarkan acara The Simpsons
karya Matt Groening. Bagi Else, latar belakang tayangan
kartun tersebut membantunya mendapatkan atmosfer khusus
dari adegan tersebut.
Beberapa tahun kemudian, ketika ia akhirnya mendapat
sponsor untuk menyelesaikan filmnya, Else berniat untuk
mengurus ijin agar dapat menggunakan cuplikan The
Simpsons tersebut.
Else kemudian menghubungi Matt Groening untuk meminta
ijin dan Groening pun menyetujuinya. Namun beliau meminta
Else untuk menghubungi terlebih dahulu perusahaan yang
memproduksi program The Simpson yakni Gracie Films.
Gracie juga ternyata tidak melihat ada masalah, namun
seperti juga Groening, mereka ingin berhati-hati dalam hal
ini. Maka kemudian mereka meminta Else untuk menghubungi
Fox Entertainment.
Kemudian Fox mengatakan, “Ada dua hal yang terjadi.
Pertama, kami baru tahu bahwa Matt Groening tidak memiliki
karya ciptaannya sendiri atau paling tidak seseorang (di Fox)
percaya bahwa Groening tidak berhak atas ciptaannya
sendiri.” Dan yang kedua, “Fox meminta 10.000 dolar
sebagai biaya lisensi karena Else menggunakan klip empat
setengah detik dari tayangan The Simpsons… yang muncul
tidak sengaja, yang kebetulan terekam di sudut kamera.”
Rebecca Herrera yang menurut Else adalah direktur utama
untuk urusan lisensi mengatakan “Dibutuhkan 10.000 dollar
untuk menggunakan sebuah klip pendek dari The simpsons
yang terekam di sudut pengambilan gambar film dokumenter
tentang karya Wagner yang berjudul Ring Cycle (The Ring).”
Yang lebih mengherankan Herrera berkata pada Else, “Dan
101
jika anda mengutip perkataan saya, anda akan berurusan
dengan pengacara saya.”
Pada saat-saat terakhir sebelum film itu akan diluncurkan,
Else akhirnya mengganti tayangan di TV tersebut secara
digital dengan klip dari film lain yang pernah dibuatnya 10
tahun sebelumnya, The Day After Trinity.
Namun ketika para pengacara mendengar cerita tentang Else
dan Fox, yang pertama kali ada dipikiran mereka adalah
“penggunaan wajar” (fair use).
Kasus antara Bottlesmoker dengan konsumen yang
menggunakan karya musik Bottlesmoker untuk proyek komersial
tersebut bisa diajukan dan dibawa ke ranah hukum, sama seperti pada
kasus Else dengan Fox. Tetapi yang terjadi disini ialah ketidakmauan
dan kurangnya inisiatif dari Bottlesmoker untuk mengajukan kasus ini
ke ranah hukum. Padahal dengan jelas, karya musik Bottlesmoker
tersebut telah dilisensikan oleh Lisensi Creative Commons, yang
lembaga dan ide dari Creative Commons itu sendiri telah tercatat di
Ditjen HKI.
Dalam tatanan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum
yang tinggi dan insiatif untuk menempuh jalur hukum, sebaiknya
Bottlesmoker berani melakukan hal-hal yang membuat Bottlesmoker
kehilangan kesempatan untuk memberikan status yang jelas kepada
karya yang telah digunakan oleh pihak pembuat iklan komersial
tersebut. Bottlesmoker juga memiliki kesempatan untuk membuat
pergerakan baru yang mungkin belum pernah dilakukan oleh pencipta
(musisi) lain.
Karena menurut salah satu narasumber, yakni sarjana hukum
lulusan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Asri Hening,
jalur hukum sebetulnya dapat dengan mudah diakses jika
pencipta menemukan kasus pelanggaran seperti diatas serta
dapat membuktikannya secara hukum. Sebetulnya masyarakat
Indonesia saat ini membutuhkan suatu terobosan hukum yang
102
berdampak pada meningkatnya kesadaran hukum dalam
masyarakat umum lain “apa yang harus dilakukan jika hal
tersebut diatas terjadi”. Karena undang-undang telah jelas
mengatur peredaran dan penggunaan karya dalam Undang-
Undang tentang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002. Lembaga
dan perangkat lain yang bisa mendukung terpecahkannya
masalah serupa pun sudah tersedia. Akan tetapi yang terjadi
dilapangan adalah kurang pedulinya masyarakat, pencipta
dan para penegak hukum yang berwenang, untuk bertindak
melakukan sesuatu jika hal tersebut berhubungan dengan
Musik. Padahal pada sektor lain, katakanlah Logo sebuah
Perusahaan. Kasus untuk logo perusahaan ini sudah cukup
terkenal dimasyarakat. Seperti misalnya, logo Coca-Cola
yang diselewengkan menjadi Coca-Cora yang kemudian
menjadi sebuah logo dari perusahaan minuman lain. Barulah
masyarakat industri mau mengajukannya ke ranah hukum.
Hal tersebut membuat penulis berpikir, bahwa harus ada
keuntungan materi tersendiri yang didapatkan, baik kepada pihak yang
dirugikan maupun pihak yang berwenang dalam mengungkap
kebenaran. Semua kembali kepada Hak Moral dan Hak Ekonomi. Disini
terlihat seperti dari pihak manapun, di publik Indonesia, masing-masing
masih merasa kurang terpenuhi dari kedua hak yang berhubungan
dengan Karya Cipta tersebut.
Fenomena ini sama seperti yang terjadi pada penyalinan besar-
besaran di pasar Louis Vuitton. Boon (2010: 30) menyatakan
Demikian halnya dengan logo monogram terkenal Louis
Vuitton (LV) yang meskipun mengatakan “Louis Vuitton”,
sebenarnya itu adalah hasil perkembangan Georges, anak
Vuitton, empat tahun setelah wafatnya sang ayah. Maka ini
menandakan ketidakhadiran ketimbang kehadiran “Louis
Vuitton”. Ketika Georges mengajukan “pemalsu” desain
ayahnya ke pengadilan (mengenai “pemalsuan” logo LV), si
103
“pemalsu” memperlihatkan sebuah buku tua pembuat kain
untuk membuktikan bahwa nyatanya sang ayahlah yang telah
mengkopi desain-“nya” dari orang lain; maka “keaslian”
yang Georges perjuangkan ternyata juga sebuah kopi yang
lain juga. Selanjutnya ada klaim yang menyatakan bahwa logo
monogram itu sendiri merupakan kopi dari berbagai macam
sumber, termasuk desain-desain Jepang (jelas bahwa hasrat
di belakang pengindeksan logo ini terkait dengan
pertumbuhan pasar Jepang) dan kertas dinding di dapur
keluarga Vuitton.
Jadi, yang dapat penulis kemukakan dari fenomena diatas
adalah bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan karya cipta
sebaiknya diagendakan, setiap detil-detil perjalanan dari karya cipta
tersebut. Seperti misalnya, terlebih dahulu mendaftarkan karya cipta
kepada pihak berwenang, sebelum karya cipta tersebut diklaim menjadi
hak milik atau hak cipta orang lain. Badan atau lembaga yang
berwenang itu pun harus sigap dan tidak menyepelekan urusan karya
cipta, karena dampak yang terjadi setelah ada sengketa akan lebih buruk
daripada mencegahnya terlebih dahulu dengan pengarsipan karya cipta
dengan baik.
Kemudian menurut data observasi penulis pada saat
wawancara dengan Ari Juliano, menyimpulkan:
Lessig pada dasarnya menginginkan sebuah budaya dimana
ketika ada seseorang membuat karya dan berkreasi dengan
bebas, kemudian membagikan karyanya ke publik untuk
kepentingan pembuatan karya baru yang lebih baik lagi,
secara berkesinambungan hal tersebut akan bermanfaat
dalam perkembangan budaya dan peradaban.
Creative Commons mencoba merubah pola pikir dan
perlakuan Hak Cipta yang “ketat” juga terbatas (restricted,
pen) serta mengatur terlalu banyak larangan. Sedangkan yang
dimaksud dengan Hak Cipta Ketat adalah ketika semua
104
pencipta menyembunyikan dan membatasi pemakaian kepada
karya yang ia telah buat. Hal tersebut akan menyebabkan
tidak berkembangnya peradaban kearah yang lebih baik lagi.
Lessig menginginkan karya-karya yang telah dibuat,
disebarkan dan dibagikan secara “bebas”. Tetapi hal tersebut
berlaku, tentu saja dengan syarat dan ketentuan yang
didapatkan dari Lisensi Creative Commons.
Pemikiran tersebut baik, hanya tinggal cara penyampaian dan
pendedikasian terhadap publik pengguna karya yang harus sedikit
diperhatikan kembali. Sepertinya fenomena seperti diatas bisa dikaitkan
dengan masalah pendidikan dan pensosialisasian tentang “karya cipta
dan hak cipta” yang harus lebih diperhatikan dan dikembangkan lagi
oleh lembaga berwenang.
4.2.3. Akses Pencipta dan Pengguna Karya
Lisensi Creative Commons telah memudahkan pencipta dan pengguna
karya dalam ranah internet dengan memberikan akses secara bebas kepada
karya, yang telah diunggah di Netlabel masing-masing pencipta, sesudah karya
tersebut dilisensikan dengan lisensi Creative Commons.
Pencipta dan pengguna karya dapat mengakses karya yang telah
dilisensikan dengan lisensi Creative Commons salah satunya dengan
mengunjungi situs jaringan resmi Creative Commons dengan alamat laman
http://creativecommons.org/about (diakses 28 Mei 2014) serta karya-karya
lainyang telah diunggah di ranah internet terdapat pada laman
http://search.creativecommons.org/ (diakses 28 Mei 2014). Pada laman
tersebut, Creative Commons menyertakan pula sebuah mesin pencari untuk
mempermudah pengguna dalam menemukan karya-karya yang telah diunggah
di internet.
Ada beberapa situs lain yang telah menyertakan Creative Commons
sebagai lisensinya dalam penggunaan dan penyebaran karya, khususnya karya
musik. Pada ranah karya musik di Indonesia, biasanya karya musik yang telah
105
diciptakan akan dipublikasikan oleh pencipta/artis pada situs web kepunyaan
sebuah netlabel. Sebagai contoh, Bottlesmoker merilis albumnya pada tahun
2012 yang berjudul Let’s Die Together in 2012 (B-Sides & Rarities Album) pada
dua netlabel sekaligus, yakni Misspelled Records dan Hujan Rekords.
Gambar 4.12. Tautan Unduh album dari Bottlesmoker - Let’s Die Together In 2012 (B-Sides
& Rarities Album) (sumber: http://bottlesmoker.asia/download/lets-die-together-in-2012-b-
sides-rarities-album/, diakses 12 Mei 2014)
Adapun tampilan pada kedua situs resmi dari netlabel perilis album
Bottlesmoker tersebut yakni;
106
Gambar 4.13. Tampilan situs resmi dari Misspelled Records dalam tautan unduh dari album
Bottlesmoker - Let’s Die Together In 2012 (B-Sides & Rarities Album) (sumber:
http://misspelledrecords.bandcamp.com/album/bottlesmoker-lets-die-together-in-2012, diakses
12 Mei 2014)
Gambar 4.14. Tampilan situs resmi dari Hujan Rekords dalam tautan unduh dari album
Bottlesmoker - Let’s Die Together In 2012 (B-Sides & Rarities Album) (sumber:
https://archive.org/details/hujan018, diakses 12 Mei 2014)
Cara yang dilakukan oleh Bottlesmoker, yang membawa serta lisensi
Creative Commons, dengan karyanya yang telah diunggah di netlabel terkait ini
107
dapat dikaitkan kepada teori Direct Marketing oleh Kottler dan Armstorng
(2008), serta definisi direct marketing oleh Belch dan Belch yang dikutip oleh
Kennedy dan Soemanagara (2006) yang menyatakan,
Bahwa pasar sasaran yang dituju merupakan hasil penyaringan dari
proses segmentasi yang selektif, sehingga pasar sasaran yang dipilih
adalah mereka yang mewakili kedekatan dengan produk dan layanan
yang ditawarkan.
Bahwa pemasar atau komunikator telah menyiapkan informasi yang
lengkap sesuai dengan apa yang dibutuhkan, dan kemungkinan
jawaban atas serangkaian informasi mengenai produk dan layanan
yang ditawarkan (solusi).
Akan tetapi yang akan terjadi pada hasil pemasaran yang dilakukan oleh
Bottlesmoker tersebut, hanya akan mendapatkan pasar yang statis dikarenakan
hasil penyaringan dari proses segmentasi yang selektif tersebut. Tetapi
Bottlesmoker akan memberikan kesempatan kepada pasar sasaran untuk
menilai dan menimbang suatu informasi yang memungkinkan proses
komunikasi yang berulang-ulang.
4.2.3.1. Penggunaa Lisensi Creative Commons
Apa saja yang sebenarnya dilakukan oleh para pengguna
lisensi Creative Commons? Apa perkerjaan tetap meraka? Serta apa
yang bisa mereka lakukan dengan lisensi Creative Commons? Kim
(2008: 192) telah membuat penelitian untuk menginvestigasi siapa saja
yang melisensikan karya mereka dibawah Lisensi Creative Commons,
yang memang tidak memiliki ketertarikan tinggi terhadap penghasilan
finansial pada karya mereka yang berhak cipta. Survey berbasis web
mengungkap pada 280 pengguna lisensi, dan sebanyak 246 (hampir
90%) mengatakan bahwa mereka melisensikan karya mereka dengan
Lisensi Creative Commons secara indivual, sementara 17 dari mereka
sebagai organisasi non-profit dan 17 lainnya sebagai koperasi untuk
penghasilan (as a corporation profit). Dari data bahwa 90% pengguna
Lisensi Creative Commons memiliki hak kepemilikannya terhadap
karya ciptanya msing-masing, memberikan saran bahwa Lisensi
108
Creative Commons ini adalah cara yang paling mudah dibandingkan
dengan lisensi lain yang mempunyai proses rumit, terutama bagi para
pencipta mandiri dengan penghasilan terbatas.
Kemudian Kim (2008) juga menyertakan data bahwa ada 4
karakter pengguna lisensi Creative Commons secara umum, yakni;
1. Profesional Komputer (28.6 %)
2. Pelajar (18.2 %)
3. Seniman (13.6 %), dan
4. Tenaga Pengajar (9.3 %)
Profesional komputer disini adalah pekerjaan yang paling
banyak mendapatkan presentase karena ketertarikannya terhadap
perangkat-perangkat yang berhubungan dengan komputer serta
pengertian yang luas terhadap dunia perkomputeran. Profesional
komputer berperan serta dalam memberikan inspirasinya untuk Creative
Commons dengan terlebih dulu membentuk Lembaga Perangkat Lunak
Bebas (Free Software Foundation) Lisensi GNU. Profesional komputer
dapat dengan mudah mengaplikasikan fungsi teknis dari lisensi CC
karena mereka memang akrab dengan teknologi komputer.
Peringkat kedua paling banyak menggunakan lisensi Creative
Commons yakni pelajar yang telah menjadikan Lisensi Creative
Commons popular dikalangan pemuda-pemudi. Hal ini dikarenakan
banyak dari mereka telah membuat kemudian mempublikasikan karya-
karyanya melaui internet. Banyak juga dari kalangan mahasiswa telah
terlibat langsung dalam pergerakan berbagi-file berbentuk karya musik
di internet (Kim: 2008), dimana dapat membuat para mahasiswa
tersebut sedikit banyak peduli terhadap konflik pada perlindungan hak
cipta di internet yang secara berkala menyegerakan mereka
menggunakan lisensi Creative Commons untuk mensupport “visi
kebijakan publik”.
Kemudian 14% dari jawaban responden mengatakan, bahwa
mereka seniman, dalam hal ini mereka sebagai kumpulan yang memiliki
109
sudut pandang “visi milik pribadi”, yang berpikir bahwa lisensi Creative
Commons bukan pilihan terbaik untuk para seniman (J.M. Saffer,
personal communication, 16 Maret 2005).
Kemudian Kim (2008: 193) membuat pertanyaan lanjutan
(follow-up question) dari data tersebut dan menghasilkan data, 71
pengguna lisensi Creative Commons (25.4 %) mengatakan meraka
adalah seniman professional (musisi, penulis, fotografer, pelukis,
pembuat disain, dan lain-lain). Dari 71 seniman professional tersebut,
hanya 38 orang yang menggunakan lisensi Creative Commons memilih
opsi “seniman” untuk mendiskripsikan perkerjaan terdekat meraka pada
saat itu. Karena pada saat yang bersamaan, mereka juga bekerja sebagai
professional komputer, tenaga pengajar, pelajar dan media professional.
Dari data diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa masih
banyak pencipta karya (termasuk seniman) yang tidak termasuk
kedalam profesional komputer. Adapun pencipta karya yang mengklaim
dirinya sebagai seniman, cenderung berada di visi milik pribadi, dengan
mempunyai pemikiran bahwa lisensi Creative Commons bukan sebuah
jalan yang dapat melindungi karya ciptanya untuk disebarkan ke media
internet.
4.2.4. Direct Marketing dalam Freeware
Seperti yang dilakukan oleh para penggagas dan pemasar perangkat
lunak bebas (freeware), yang menyertakan Lisensi Creative Commons CC BY-
SA atau akrab disebut dengan lisensi “Copyleft”, Bottlesmoker juga melakukan
hal yang sama, seperti pernyataan Angkuy pada kesempatan observasi
saya memang menyukai software-software yang dibagikan secara bebas
oleh para penciptanya. Bayangkan mereka (profesional komputer) yang
telah meluangkan pikiran, tenaga serta uang yang mereka punya untuk
110
membuat sebuah perangkat lunak, yang pada akhirnya hanya akan
dimasukan kedalam sebuah toko perangkat lunak digital di internet,
kemudian dibagikan ke publik dengan tidak memungut biaya sepeser
pun (free). Padahal software yang mereka buat (game, prosesor efek
digital untuk musik, peta, media sosial dan lain-lain) bukan software
yang murahan. Saya tidak jarang merasa terhibur dengan game yang
telah saya unduh dari internet. Maka dari itu saya pun tergugah untuk
membuat musik, kemudian membagikannya secara bebas, sama seperti
perangkat-perangkat lunak ciptaan profesional komputer tersebut.
Gambar 4.15. Tampilan beberapa Perangkat Lunak Bebas (freeware) pada salah satu Toko
Perangkat Lunak Digital (sumber: iTunes App Store, diakses 13 Mei 2014)
Dalam teori pemasaran oleh Soemanagara (2006: 26), terdapat teori
Direct Marketing yang berbunyi “direct marketing (pemasaran langsung)
adalah sistem dari pemasaran, oleh sebuah organisasi yang
mengkomunikasikan secara langsung dengan konsumen sebagai target, untuk
menumbuhkan respon atau transaksi tertentu”. Dasar pemikiran tersebut yang
membuat penulis berpikir bahwa, Angkuy bersama Bottlesmoker melakukan
salah satu kegiatan direct marketing tersebut, melalui penyebaran karya musik
Bottlesmoker ke internet, dimana karya musik tersebut dapat langsung diakses
oleh pengguna (konsumen) yang ingin mendengarkan karya musik
Bottlesmoker.
111
Pada kesempatan observasi, penulis juga mendapatkan data bahwa,
pernah pada suatu saat, ketika Bottlesmoker baru memulai karirnya didunia
musik, Bottlesmoker melakukan direct marketing yang sangat gamblang.
Maksudnya, Bottlesmoker membuat CD (dengan cara burning audio yang
sudah berbentuk mp3 dengan piranti lunak) untuk dibawa ke venue tempat
Bottlesmoker akan mementaskan karyanya, sementara pada kesempatan yang
sama Bottlesmoker juga membagi-bagikan CD hasil burning tersebut.
Fenomena tersebut dapat dikatakan sebagai fenomena D.I.Y. (Do It Yourself).
Cara tersebut ternyata masih kurang efektif mengingat keterbatasan
Bottlesmoker dalam mengenal khalayak yang lebih luas, yang menyebabkan
Bottlesmoker masih kurang dikenal. Jadi Bottlesmoker mulai berpikir lebih
keras, kemudian mendapatkan ide untuk membagikan karya musik
Bottlesmoker “langsung” ke komputer operator dibeberapa warung internet
yang terdapat di sekitar tempat tinggal Bottlesmoker.
Cara terakhir yang Bottlesmoker lakukan ternyata berhasil. Baru pada
tahun 2008, pada album Before Circus Over, Bottlesmoker mulai cukup
terkenal, terlihat dari jadwal pentas Bottlesmoker yang mulai memasuki
kategori padat.
112
Gambar 4.16. Gambar Cover Album (Album Artwork) dari album Bottlesmoker – Before
Circus Over (sumber: http://bottlesmoker.asia/download/before-circus-over-neovinyl-records-
2006-2/, diakses 13 Mei 2014)
Dapat penulis kaji disini, bahwa direct marketing seperti yang dilakukan
oleh Bottlesmoker, merupakan kegiatan yang menguras banyak tenaga dan
pikiran. Jadi tentu saja melakukan direct marketing di internet merupakan
sebuah efektifitas yang dapat memangkas biaya, dibandingkan dengan
melakukan direct marketing, seperti pada cerita Bottlesmoker yang telah
penulis kemukakan diatas.
Kejadian seperti diatas mengingatkan pada Belch dan Belch:
Bahwa pasar sasaran telah mengenal produk dan layanan sebelumnya
melalui saluran media massa atau media promosi lainnya.
113
Dalam artian, Bottlesmoker telah mengijinkan pasar sasaran untuk
“menyicipi” karya musik Bottlesmoker sebelum pasar sasaran tersebut
membelinya, dalam kaitan untuk memenuhi hak ekonomi dari karya musik yang
telah Bottlemsoker ciptakan. Kemudian:
Bahwa pasar sasaran yang dituju merupakan hasil penyaringan dari
proses segmentasi yang selektif, sehingga pasar sasaran yang dipilih
adalah mereka yang mewakili kedekatan dengan produk dan layanan
yang ditawarkan.
Erat kaitannya dengan fenomena Bottlesmoker yang terlebih dahulu
membidik pasar sasaran dengan tepat dengan cara segmentasi yang selektif,
sehingga Bottlesmoker mengetahui betul siapa-siapa saja dari pasar sasaran
tersebut yang mewakili kedekatan dengan karya musik ciptaan Bottlesmoker.
Serta:
Bahwa direct marketing juga merupakan sebuah proses yang
memberikan kesempatan pada pasar sasaran untuk menilai dan
menimbang suatu informasi atau produk dalam suatu proses
pengambilan keputusan, memungkinkan proses komunikasi dilakukan
berulang-ulang (follow-up process).
Bottlesmoker mengembalikan pendapat dan prakiraan publik dalam hal
ini pasar sasaran, untuk menilai dan menimbang karya musik dan penampilan
Bottlesmoker di panggung, yang kemudian Bottlesmoker dan pasar sasarannya
akan diikuti dengan proses berkelanjutan dan berulang-ulang, selama pasar
sasaran tersebut terus mengikuti perkembangan Bottlesmoker.
114
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil observasi dan pembahasan yang telah dilakukan
oleh penulis, tentang “Peranan Lisensi Creative Commons pada Pemasaran
Karya Musik di Indonesia”, maka dalam sub-bab ini peneliti akan
mengutarakan kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut:
1. Dari segi perkembangan ilmu pengetahuan, Lisensi Creative
Commons dapat membantu peran distribusi karya musik, agar
penyaluran dan penyebaran karya, khususnya dalam ranah
internet, lebih terkoordinir dan berkembang lebih luas lagi. Lebih
berkembang lebih luas lagi, artinya jika beberapa karya (musik,
fotografi, film, gambar, tulisan, dll) saja dilisensikan dibawah
lisensi Creative Commons sudah dapat membuat perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perspektif sempit, seperti
mudahnya akses terhadap karya cipta oleh khalayak yang
membuat khalayak lebih kreatif mengembangkan ide-idenya,
bayangkan jika semua karya diranah internet tersebut telah
dilisensikan dibawah lisensi Creative Commons. Hal demikian
akan dapat membuat peradaban manusia umumnya, peradaban di
ranah internet khususnya, lebih kreatif dan berkembang lagi.
Kemudian lebih terkoordinir lagi, artinya jika karya-karya yang
sudah dilisensikan tersebut dijadikan sebuah bank penyimpanan
data, publik yang mencari data untuk kebutuhannya berkarya
dapat dengan mudah mengunjungi situs jaringan resmi Creative
Commons untuk mengakses data yang diperlukan.
115
Kegiatan Creative Commons Indonesia pada saat ini sudah sampai
kepada proses sosialisasi kepada pihak-pihak komunitas dan
belum tersosialisasikan sampai ke pihak pemerintahan Indonesia.
Menurut Ari Juliano misi Creative Commons selanjutnya adalah
berusaha untuk meneruskan penyuluhan tentang lisensi Creative
Commons ke ranah pemerintahan. Cita-cita Creative Commons
Indonesia adalah mewujudkan penyebarluasan informasi dan
transparansi data pemerintahan kepada khalayak, sama seperti
yang telah dilakukan oleh White House, Amerika Serikat. White
House memiliki sistem Open Government. Menurut Ari Juliano
Open Government adalah sebuah keadaan dimana semua data
tentang pemerintahan yang menyangkut kesejahteraan publik,
telah mudah diakses hanya melalui internet. Jika semua data
pemerintahan sudah tertransparansikan ke publik, maka tidak akan
ada lagi kesalahpahaman yang terjadi antara hubungan pemerintah
dengan rakyatnya.
2. Creative Commons Indonesia dengan Lisensi Creative Commons-
nya adalah sebuah fenomena penolakan publik terhadap sistem
kapitalisme kontemporer yang berujung pada pemikiran sosialis
serta mengedepankan sistem berbagi terhadap sesama. Hal
tersebut membuat Creative Commons bersama lisensinya
direkomendasikan oleh UNESCO (United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization) atau Organisasi Pendidikan,
Keilmuan, dan Kebudayaan PBB.
Lisensi Creative Commons tidak membantu Bottlesmoker
sepenuhnya dalam penyebaran dan pendistribusian karya. Karena
Bottlesmoker telah melakukan sistem berbagi-file secara “bebas”
beberapa tahun sebelum Creative Commons Indonesia
diresmikan. Akan tetapi dengan adanya Lisensi Creative
116
Commons, Bottlesmoker seperti diberikan sebuah alternatif yang
baru dan baik dalam pendistribusian karya-karyanya di ranah
internet. Hal tersebut dapat penulis kemukakan karena,
berdasarkan data yang shahih, yang penulis dapatkan dari
Bottlesmoker, adalah bahwa Bottlesmoker telah melakukan
kegiatan berbagi-file pada saat-saat pertama Bottlesmoker lahir ke
publik, yakni sekitar tahun 2006. Sedangkan Creative Commons
Indonesia baru diresmikan dalam Konferensi Creative Commons
Asia Pasifik 2012 dan Peluncuran Creative Commons Indonesia
di Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta, tanggal 10-11 November, tahun
2012.
Setelah Creative Commons Indonesia diresmikan, kemudian
Lisensi Creative Commons disosialisasikan ke publik, hal tersebut
sangat membantu Bottlesmoker dalam “penyadaran publik”
bahwa karya-karya Bottlesmoker mempunyai pemilik yang pada
saat itu pemilik atau pencipta tersebut memiliki sebuah “Hak
Cipta” yang harus diperjuangkan dan dihormati. Walaupun dalam
kenyataannya Bottlesmoker belum pernah mendaftarkan karya-
karya yang dibagikan di internet tersebut ke Direktorat Jenderal
HKI.
117
5.2. SARAN
Pada sub-bab ini, penulis akan menjabarkan beberapa saran, ide dan
gagasan pribadi penulis kepada pihak-pihak yang terkait dan terlibat dalam
penulisan karya tulis ilmiah ini. Pihak yang terkait tersebut antara lain
Bottlesmoker, Dewan Direktur dan Wakil Direktur serta pengelola Creative
Commons Indonesia secara umum, Pemerintahan, serta masyarakat luas
dalam lingkup masyarakat umum maupun masyarakat lingkup khusus
sebagai pengkonsumsi karya musik di ranah internet.
1. Pergerakan mandiri yang dilakukan oleh Bottlesmoker bisa
dikategorikan sebagai pergerakan independen yang teratur dan
berkembang. Bottlesmoker mempunyai visi yang baik dalam cara
Bottlesmoker mempresentasikan karya musik ciptaan
Bottlesmoker kepada khalayak. Hal tersebut dapat ditinjau dari
pergerakan Bottlesmoker yang langsung terjun ke lapangan
kemudian bersentuhan langsung dengan konsumen untuk
mempresentasikan karya musiknya. Tetapi di sisi lain,
Bottlesmoker kurang peduli terhadap hak ekonomi dan hak moral
yang bisa didaptkan dari karya musik yang telah Bottlesmoker
ciptakan. Hal tersebut telah dengan jelas disebutkan di undang-
undang kenegaraan yang sudah berusaha memperjuangkan kedua
hak tersebut. Alangkah lebih baiknya jika Bottlesmoker sedikit
lebih peduli lagi terhadap perihal hukum tersebut, seperti mulai
mendaftarkan karya-karya ciptaan Bottlesmoker ke lembaga yang
berwenang menangani masalah ciptaan ini. Karena seperti yang
telah penulis ketahui beberapa waktu yang lalu, bahwa
pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual ke Direktorat Jenderal HKI
adalah sebuah bentuk kepedulian yang besar terhadap sebuah
karya cipta. Sebuah karya cipta yang sudah terdaftarkan di Ditjen
HKI berpotensi menghasilkan pemasukan. Ari Juliano menulis
dalam Blognya:
118
“biaya yang dikeluarkan untuk pendaftaran HKI tersebut
pada dasarnya bukanlah pengeluaran semata, namun
merupakan investasi bagi pelaku usaha. Hal ini karena selain
menambah jumlah aktiva dalam laporan keuangan, juga
berpotensi menghasilkan pemasukan jika dikemudian hari
mendapatkan royalti dari hasil melisensikan atau
mewaralabakan HKI tersebut kepada pihak lain, atau ketika
HKI dialihkan kepada pihak lain dengan nilai yang lebih besar
dari nilai perolehannya.”
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendaftaran atas karya-
karya ciptaan Bottlesmoker ke lembaga berwenang bukan semata-
mata pemborosan yang harus dihindari. Melainkan bisa menjadi
salah satu sumber pendapatan dan investasi untuk masa yang akan
datang.
2. Pengesahan yang telah dilakukan oleh dewan pengurus serta
pengelola Creative Commons Indonesia dalam meresmikan
Lisensi Creative Commons sebagai lisensi yang syah secara
kenegaraan adalah sebuah langkah awal yang sangat baik dalam
mensosialisasikan lisensi ala penduduk Amerika Serikat ini.
Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh dewan pengurus
dan pengelola Creative Commons Indonesia adalah
mensosialisasikan lebih luas kepada publik, sampai pada suatu
keadaan dimana sebagian besar publik telah mengenal Lisensi
Creative Commons dengan baik. Kemudian disela-sela
pensosialisasian tersebut, Creative Commons Indonesia
seharusnya sudah bisa mempresentasikan karya-karya yang telah
dilisensikan oleh Lisensi Creative Commons dengan klasifikasi
data yang terorganisir dengan baik. Hal tersebut bertujuan agar
khalayak yang ingin mengetahui contoh karya yang telah
119
menggunakan Lisensi Creative Commons dapat diakses dengan
mudah.
3. Karena Creative Commons Indonesia telah susah payah
membangun sebuah lembaga yang mapan dan baik, tugas kita
sebagai masyarakat yang berbudaya luhur, salah satunya adalah
dengan mulai menyadari bahwa Undang-undang Hak Cipta dan
Lisensi yang diperjuangkan oleh Pemerintahan dan Creative
Commons Indonesia merupakan sebuah bentuk kepedulian juga
keprihatinan terhadap masyarakat kita yang belum memiliki sudut
pandang yang baik untuk hal semacam ini. Agar lebih mengerti
dan peduli terhadap fenomena budaya yang sedang panas terjadi
dipermukaan, kita sebagai masyarakat sadar hukum seharusnya
lebih mengkaji kemudian ikut mengembangkan dengan belajar
lebih banyak mengenai masalah ini.
4. Creative Commons Indonesia seharusnya lebih bisa
mengalokasikan dana pensosialisasian dari Ford Foundation yang
telah dibicarakan dengan penulis, terhadap perkembangan serta
penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi dengan lebih baik
lagi. Dikarenakan jika pergerakan Creative Commons Indonesia
untuk saat ini hanya pada titik dimana Creative Commons
Indonesia dikenali dan disadari keberadaannya oleh sebagian kecil
masyarakat saja, kemungkinan besar Creative Commons
Indonesia hanya akan menjadi sebuah lembaga yang tidak
berperan besar dalam perkembangan budaya yang lebih beragam
dan bermartabat, seperti tujuan awal didirikannya Creative
Commons Indonesia yang tertera dalam visi dan misi Creative
Commons Indonesia, yakni:
Visi: mewujudkan sepenuhnya potensi internet — akses
universal terhadap penelitian dan pendidikan, partisipasi
120
penuh dalam kebudayaan — untuk menuju era baru
perkembangan, pertumbuhan, dan produktivitas
Misi: mengembangkan, mendukung, dan menyediakan sarana
infrastruktur hukum dan teknis yang memaksimalkan
kreativitas, keinginan untuk berbagi karya, dan inovasi digital.
5. Creative Commons Indonesia mempunyai cita-cita yang baik
untuk mulai mensosialisasikan dan menerapkan sistem Lisensi
Creative Commons terhadap sistem pemerintahan Indonesia yang
sedang mengelola masyarakat luas. Cita-cita tersebut akan lebih
berjalan serta teraplikasikan dengan baik jika pemerintahan
Indonesia ikut mendukung dan mulai melakukan riset-riset
berkaitan dengan penerapan Lisensi Creative Commons dalam
sistem pemerintahannya. Sebuah contoh dapat penulis kemukakan
dari hasil wawancara dengan Ari Juliano.
Pemerintah Indonesia pada tahun 2009-2010 telah memulai
sebuah gerakan pembaharuan dengan membuat sebuah buku
pelajaran untuk siswa sekolah dalam bentuk elektronik dengan
nama Buku Sekolah Elektronik (BSE). BSE ini mempunyai
sebuah nilai yang lebih efisien dan praktis jika dibandingkan
dengan buku biasa. Pemerintah membeli buku-buku dari
penerbit, kemudian membeli hak cipta dari masing-masing
pemilik ciptaan buku tersebut, kemudian merubah bentuk buku
konfensional menjadi BSE berbentuk data. Kemudian BSE
disebar ke daerah-daerah dalam bentuk digital.
Namun masalahnya terdapat dalam hal Lisensi. Lisensi yang
digunakan untuk penyebaran BSE ini tidak jelas. Pemerintah
membagi-bagikan BSE secara gratis tetapi konten-konten
yang terdapat pada BSE tidak boleh diubah-ubah. Sedangkan
konten dari BSE sendiri adalah pengetahuan-pengetahuan
121
yang tidak statis dan dapat berkembang seiring dengan
perkembangan jaman.
Ada sebuah proyek dari pemerintah Amerika Serikat yang
bernama Open Educational Resources (OER). OER
menyediakan beberapa sumber pengetahuan yang sudah
dapat diakses oleh siapa pun, dimana pun, tetapi sudah
terlisensi dengan jelas. Lisensi Creative Commons.
Dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah seharusnya lebih
lugas dan tajam dalam menilik segala fenomena budaya seperti ini,
agar tidak terkesan hanya sekedar “mengaplikasikan” saja.
Kemudian secara berkesinambungan gerakan seperti ini dapat
berperan serta dalam menciptakan sebuah kondisi dimana
masyarakat umum juga turut andil dalam perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.