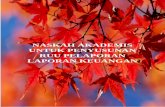Penelitian tentang RUU Desa
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Penelitian tentang RUU Desa
A. Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Desa dalam
Mewujudkan Kemandirian Pemerintahan Desa Melalui Penguatan
Demokrasi Partisipatif Masyarakat Desa (analisis normatif Bab XI
Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
serta Rancangan Undang-Undang tentang Desa)
B. Latar Belakang Masalah
Desa, yang juga disebut sebagai Nagari di Sumatera Barat,
Lembang di Sulawesi Selatan, Kampung di Kalimantan Selatan,
ataupun Negeri di Maluku, dan juga nama-nama lainnya adalah
istilah yang diperuntukkan bagi persekutuan penduduk pada
masyarakat yang terendah di seluruh wilayah Indonesia. Dalam
praksisnya, ada begitu banyak pengertian mengenai desa, namun,
secara garis besar, jika ditarik satu kesimpulan mengenai
pengertian-pengertian tersebut, maka desa akan meliputi kesatuan-
kesatuan pemerintahan, kesatuan ekonomi, kesatuan kulturil dan
tradisionil yang kokoh dan kuat, dan disana-sini sudah atau
sedang mengalami perubahan maju ke arah perkembangan sebagai
akibat pengaruh perkembangan teknologi.1
1 Sumber Saparin, “Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), hlm. 11
1
Selama ini, desa menjadi bahasan yang selalu menarik, tak
lain karena desa, penduduk, system sosial, dan pemerintahannya
selalu menjadi komoditi yang sering dibicarakan. Keberadaannya
dikaji para pakar dalam forum-forum ilmiah, didesain oleh para
pengambil kebijakan, disakralkan oleh sebagian sosiolog dan
antropolog, kemudian menjadi proyek oleh pejabat dan pemegang
kekuasaan, dan dikeruk kekayaannya oleh para pemilik modal. Akan
tetapi, kesemuanya tidak membuat sebuah dampak signifikan dalam
hal kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri sejak dulu sampai
sekarang. Masyarakat desa tetap saja miskin dan terbelakang dan
terkesan tak ada kemajuan atau perbaikan yang berarti.2
Desa masuk dalam entitas khusus yang diatur dalam satu bab
khusus pada Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah. Desa diatur dalam Bab XI yang berisi Enam Bagian dan 17
pasal. Hal itu menunjukkan posisi desa sebagai bagian penting
dalam tata kenegaraan di Indonesia. Menurut UU No. 32 Tahun 2004,
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yurisdiksi , berwenang untuk mengatur dan mengurus tugas
2 Hanif Nurcholis, “Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”. (Jakarta: Erlangga, 2011)
2
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem
pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota.
Benar bahwa istilah otonomi desa sudah menjadi bagian dari
kehidupan kenegaraan di Indonesia, khususnya dengan keluarnya
berbagai kebijakan Negara tentang desa. Kebijakan-kebijakan
tersebut selaras dengan kebijakan Negara tentang desentralisasi
yang memang menjadi topik umum dalam regulasi mengenai otonomi
daerah. Namun, dalam berbagai kebijakan yang ada, desa lebih
ditempatkan sebagai bagian terbawah dari penyelenggaraan
pemerintahan nasional, yang menerima kewenangan dari pusat. Hal
ini lah yang membuat desa seakan kurang mandiri. Selain itu,
pergantian undang-undang yang selama ini terjadi tidak mengarah
pada perubahan kedudukan desa yang lebih jelas, justru memicu
bongkar pasang yang menimbulkan masalah-masalah baru.
Keadaan diperparah dengan melihat sebuah fakta bahwa sejak
diundangkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
sampai detik ini belum keluar sebuah regulasi yang mengatur
secara khusus tentang pemerintahan desa. Sebagai contoh, selama
3
ini perubahan mengenai regulasi tentang desa hanya berkisar atau
hanya menyangkut substansi-substansi tertentu saja, seperti
penguatan posisi kepala desa, pengisian sekretaris desa dari PNS,
dan bahkan adanya pemandulan fungsi BPD (Badan Permusyawaratan
Desa). Selebihnya, tidak atau belum ada inovasi-inovasi baru
tentang penguatan dari system pemerintahan desa tersebut.
Kekurangan lain dalam hal pengaturan tentang desa yang
tertuang dalam UU No. 32 juga menyangkut ketidak jelasan tentang
pengaturan tata kewenangan antara pemerintah, pemerintah daerah,
dan desa. UU No 32 Berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi
luas yang dianut oleh UU No. 32/2004, Pemerintah hanya
menjalankan lima kewenangan, dan diluar lima kewenangan itu
menjadi kewenangan daerah. Dengan demikian konsepsi dasar yang
dianut UU No. 32/2004, otonomi berhenti di kabupaten/kota.
Kosekuensinya, pengaturan lebih jauh tentang Desa dilakukan oleh
kabupaten/kota, dimana kewenangan Desa adalah kewenangan
kabupaten/kota yang diserahkan kepada Desa.3
Nilai demokrasi Desa juga diperdebatkan oleh banyak
kalangan. Pertanyaan yang selalu muncul adalah bagaimana makna
3 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desa, hal. 3
4
demokrasi substansial dan demokrasi prosedural yang tepat dan
relevan dengan konteks lokal Desa? UU No. 32/2004 mengusung nilai
demokrasi substansial yang bersifat universal seperti
akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Tentu banyak pihak
menerima nilai-nilai universal ini, mengingat Desa sekarang telah
menjadi institusi modern. Tetapi tidak sedikit orang yang selalu
bertanya: apakah nilai-nilai universal itu cocok dengan kondisi
lokal, apakah orang-orang lokal mampu memahami roh akuntabilitas,
transparansi dan partisipasi dengan cara pandang lokal, atau
adakah nilai-nilai dan kearifan lokal yang bisa diangkat untuk
memberi makna dan simbol akuntabilitas, transparansi dan
partisipasi. Sementara perdebatan pada aras demokrasi prosedural
terletak pada pilihan: permusyawaratan yang terpimpin atau
perwakilan yang populis.4
Dari sisi kesejahteraan, UU No. 32/2004 memang telah membawa
visi kesejahteraan melalui disain kelembagaan otonomi daerah.
Semua pihak mengetahui bahwa tujuan besar desentralisasi dan
otonomi daerah adalah membangun kesejahteraan rakyat. Pemerintah
daerah mempunyai kewajiban dan tanggungjawab besar meningkatkan
4 Ibid., hal. 4
5
kesejahteraan rakyat melalui kewenangan besar dan keuangan yang
dimilikinya. Tetapi visi kesejahteraan belum tertuang secara
jelas dalam pengaturan mengenai Desa.
Perdebatan mengenai otonomi, demokrasi dan kesejahteraan itu
parallel dengan pertanyaan fundamental tentang apa esensi (makna,
hakekat, fungsi, manfaat) Desa bagi rakyat. Apakah Desa hanya
sekadar satuan administrasi pemerintahan, atau hanya sebagai
wilayah, atau hanya kampung tempat tinggal atau sebagai
organisasi masyarakat lokal? Apakah Desa tidak bisa dikembangkan
dan diperkuat sebagai entitas lokal yang bertenaga secara sosial,
berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi dan bermartabat
secara budaya?
C. Rumusan Masalah
Dari penjelasan diatas, diperoleh beberapa masalah, yakni:
1. Bagaimana pemahaman atas hakekat desa serta pengaturan
tentang desa yang ingin dicapai melalui Rancangan Undang-
Undang tentang Desa?
2. Mengapa kemandirian pemerintahan desa dan terwujudnya
demokrasi dan kedaulatan rakyat di level desa menjadi hal
6
yang diperlukan dalam mencapai kesuksesan pembangunan di
level nasional?
D. Tujuan Penelitian
1. Untuk memahami hakekat desa serta asas dan perspektif
tentang pengaturan desa yang akan dicapai melalui
Rancangan Undang-Undang tentang Desa.
2. Untuk membuktikan hubungan antara kemandirian desa dan
kesuksesan pembangunan nasional merupakan hubungan yang
bersifat dialektis.
3. Untuk menunjukkan pengesahan terhadap Rancangan Undang-
Undang tentang Desa adalah sebuah batu loncatan besar dalam
mewujudkan kemandirian pemerintahan dan masyarakat di level
desa yang akan berpengaruh terhadap pembangunan di level
nasional.
E. Manfaat Penelitian
Kegunaan dalam penulisan laporan penelitian ini, sebagai
berikut;
1. Manfaat Teoritis
7
Penelitian ini di lakukan untuk pengembangan pengetahuan
hukum pada umumnya dan khususnya pada hukum tata negara
tentang otonomi daerah serta pemerintahan desa sebagai
ruang aktualisasinya.
2. Manfaat Praktis
Bagi para penggiat dan pihak yang peduli terhadap desa
diharapkan karya tulis ini membuka wacana serta wawasan
yang variatif dalam hal pemerintahan desa dalam perannya
sebagai sebuah sarana penguatan terhadap masyarakat desa.
Bagi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dapat menjadi
literatur yang bermanfaat bagi peneliti-peneliti akademis
lainnya yang mempunyai minat dan perhatian yang sama
terutama studi hukum tata negara.
Bagi Masyarakat di harapkan tumbuh kesadaran akan
pentingnya kemandirian pemerintahan desa, hal ini
mengingat bahwa kemandirian pemerintahan dan masyarakat
desa akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan dan
program pemerintah secara nasional.
F. TINJAUAN PUSTAKA
8
1. Tinjauan tentang Otonomi Daerah
Peneliti mengacu pada definisi otonomi daerah dalam pasal 1
angka 5 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi:
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Otonomi daerah dapat dipahami sebagai suatu proses devolusi
dalam sector public dimana terjadi pengalihan wewenang dari
pemerintahan pusat kepada pemerintahan provinsi dan
kabupaten/kota. Dengan kata lain, dalam konteks Indonesia,
otonomi daerah diartikan sebagai proses pelimpahan kekuasaan dari
pemerintahan pusat kepada pemerintahan provinsi dan
kabupaten/kota sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.5
Selanjutnya, tujuan dari otonomi daerah atau desentralisasi
ini sangat beraneka ragam, antara lain: (1) peningkatan pelayanan
masyarakat yang semakin baik, (2) pengembangan kehidupan
demokrasi, (3) keadilan, (4) pemerataan, (5) pemeliharaan
hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah
dalam rangka keutuhan NKRI, (6) mendorong untuk memberdayakan
5 Mas’us Said, “Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia”, (Malang: UMM Press, 2008), hlm. 5
9
masyarakat, (7) menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas,
meningkatkan peran serta masyarakat, serta mengembangkan peran
dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.6
Konsep mengenai otonomi daerah ini telah ada sejak zaman
Yunani Kuno. Dimana saat ini Aristoteles dan pengikutnya telah
secara tegas menekankan pentingnya distribusi dan pembagian
kekuasaan.7 Walaupun memang aplikasi dari premis ini dalam bentuk
desentralisasi baru banyak diperdebatkan, khususnya di Negara-
negara sedang berkembang pada tahun 1950 an.8
Otonomi daerah, atau sebut saja dengan desentralisasi,
didasari fakta bahwa tiada satupun pemerintah dari suatu negera
dengan wilayah yang luas dapat menentukan kebijaksanaan secara
efektip ataupun dapat melaksanakan kebijaksanaan dan program-
programnya secara efisien melalui sistem sentralisasi (Bowman &
Hampton, 1983).
Dalam konteks Indonesia, konsep mengenai desentralisasi ini
sudah menjadi cita-cita para founding fathers sejak awal. Dimana
dalam konstitusi Negara secara jelas sudah menyatakan bahwa6 Mohtar Mas’oed, “Politik, Birokrasi dan Pembangunan, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2003)7 Syarif Hidayat, “Kegamangan Otonomi Daerah”, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2004), hlm. 178 ibid
10
mereka mengharapkan Indonesia sebagai suatu Negara yang
demokratis dan terlebih desentralistis. Hal ini terjadi karena
mereka sadar, dengan berbagai macam perbedaan antar daerah, dalam
hal ini adalah tingginya variabilitas antar daerah menjadi aspek
yang membuat tidak memungkinkannya Indonesia menjadi Negara yang
sentalistis.
Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia mengalami pasang
surut sesuai dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi
di masanya. Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia mengalami
perkembangan yang berarti sejak dilaksanakannya UU 22/1999 yang
menganut otonomi luas. UU tersebut membatasi urusan pemerintahan
di tingkat pusat dan provinsi melalui Peraturan Pemerintah Nomor
25 tahun 2000 dan mengalihkan sisanya kepada kabupaten/ kota
melalui mekanisme pengakuan.9
Desentralisasi sendiri tidak dapat dilepaskan keterkaitannya
dengan demokratisasi pemerintahan. Desentralisasi harus dipahami
sebagai sebuah pilihan metode untuk mengatur proses
penyelenggaraan kekuasaan dalam suatu Negara. Tujuan yang ingin
dicapai tidak lain agar cita-cita Negara kesejahteraan (welfare
9 Ibid., hlm. 26
11
state) yaitu terwujudnya kesejahteraan rakyat (bonum commune)
dapat direalisasikan.10 Namun, dalam praksisnya, terlihat cukup
banyak pandangan yang justru terkesan menjadikan desentralisasi
sebagai tujuan dalam kehidupan kenegaraan, dan perwujudan
kesejahteraan rakyat sebagai subordinat saja.11
Ruland (1992:3) mengatakan bahwa desentralisasi, sebagai
akibat wajar dari otonomi local, dapat dilihat sebagai kontribusi
positif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, yang pada
akhirnya akan mengarah pada perkembangan sosio-ekonomi. Dan
memang, filosofi otonomi daerah sendiri seharusnya menempatkan
rakyat sebagai subjek dalam pemerintahan daerah. Moralitas dari
otonomi daerah adalah optimalisasi kinerja pelayanan public
dengan menguatkan akses rakyat dalam proses penyusunan kebijakan
pada level daerah,12
2.Tinjauan tentang Desa dan Pemerintahan Desa
Peneliti mengacu pada definisi Desa dalam Peraturan
Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa yang berbunyi:
10 Willy R. Tjandra, “Praksis Good Governance”, (Jogjakarta: Pondok Edukasi, 2006), hlm. 511 Ibid., hlm. 612 Ibid
12
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pengakuan akan otonomi desa juga ada dalam UU No.32/2004.
Dalam UU itu dijelaskan tentang definisi desa yang dimuat dalam
Pasal 1 angka 12, yakni, kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal-asul dan adat istiadat setempat yang diakui
dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal
ini sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Basis
pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintahan desan adalah
keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan
pemberdayaan masyarakat.
Selanjutnya mengenai kewenangan desa, desa mempunyai
beberapa kewenangan, yaitu: (1) Menyelenggarakan urusan
pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, (2)
Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada
desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat
13
meningkatkan pelayanan masyarakat, (3) Tugas pembantuan dari
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota,
(4) Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.
Dalam hal pemerintahan, Desa memiliki pemerintahan sendiri.
Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi
Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan
Desa (BPD). Dalam bab XI Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 diatur
mengenai hal-ikhwal tersebut. Yang pertama, Kepala Desa merupakan
pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan
yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa
jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi
untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa juga memiliki wewenang
menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama
BPD.
Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa terdiri dari
Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya. Salah satu perangkat
desa adalah Sekretaris Desa, yang diisi dari Pegawai Negeri
Sipil. Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah
Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota. Perangkat Desa lainnya
14
diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa, yang ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa. perangkat desa juga mempunyai tugas
untuk mengayomi kepentingan masyarakatnya.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga
perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan
berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari
Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama
dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota
BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1
kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak
diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat
Desa. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala
Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi
kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APB Desa), bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah.
Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan
oleh pemerintah desa didanai dari APBD. Penyelenggaraan urusan
pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Sumber
15
pendapatan desa terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Desa, (2) Bagi
hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota, (3) Bagian dari Dana
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, (4) Bantuan keuangan dari
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan, (5) Hibah dan
sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, (6) Pinjaman
desa.
APB Desa terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa
dan Pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah
perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan
APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.
Pada awalnya Desa merupakan organisasi komunitas lokal yang
mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan
mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Inilah
yang disebut dengan self-governing community. Sebutan Desa sebagai
kesatuan masyarakat hukum baru dikenal pada masa kolonial
Belanda. Desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang
dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkhis-struktural dengan
struktur yang lebih tinggi. Di Sumatera Barat, misalnya, nagari
adalah sebuah “republik kecil” yang mempunyai pemerintahan
16
sendiri secara otonom dan berbasis pada masyarakat (selfgoverning
community).13
Desa-Desa di Jawa sebenarnya juga menyerupai “republik
kecil”, dimana pemerintahan Desa dibangun atas dasar prinsip
kedaulatan rakyat. Trias politica yang diterapkan dalam negara-bangsa
modern juga diterapkan secara tradisional dalam pemerintahan
Desa. Desa-Desa di Jawa, mengenal Lurah (kepala Desa) beserta
perangkatnya sebagai badan eksekutif, Rapat Desa (rembug Desa)
sebagai badan legislatif yang memegang kekuasaan tertinggi, serta
Dewan Morokaki sebagai badan yudikatif yang bertugas dalam bidang
peradilan dan terkadang memainkan peran sebagai badan
pertimbangan bagi eksekutif.14 Uraian diatas ingin menegaskan
bahwa desa sejak awal deklarasi kemerdekaan telah diakui memiliki
kedudukan khusus dan memliki kemerdekaan sendiri (zelfbestuur).15
3. Tinjauan tentang Demokrasi Partisipatif di Desa
Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani,
“demos” berarti rakyat, dan “kratos” atau “kratein” yang berarti13 Sumber Saparin, “Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977)14 Ibid., hlm. 4615 Willy R. Tjandra, “Praksis Good Governance”, (Jogjakarta: Pondok Edukasi, 2006), hlm. 78
17
kekuasaan. Konsep dasar demokrasi berarti “rakyat berkuasa”.
Istilah demokrasi secara singkat diartikan sebagai pemerintahan
atau kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 16
Dalam buku Plato berjudul Republic, Plato merumuskan negara kota
Yunani kuno sebagai bentuk partisipasi langsung rakyat dalam roda
pemerintahan yang di representasikan dan di gerakkan oleh para
filsuf. Pandangan Plato tentang keterwakilan/representatif ini di
dasari atas pengaruh Socrates tentang moralitas kepercayaan
individu terhadap tatanan yang alamiah.17
Selepas era Yunani Kuno, muncul konsep Eropa klasik
merupakan respon atas sistem pemerintahan monarki absolut. Tokoh
demokrasi Eropa klasik antara lain; Jean Jacques Rousseau, John
Locke dan Thomas Paine. John Locke seorang filsuf dari Inggris
mengatakan negara harus di bangun di bawah kepercayaan rakyatnya.
Di Indonesia sendiri, sejak dulu sudah dipraktekkan ide
tentang demokrasi ini, dan hal ini dimulai dari tingkat desa.
dalam demokrasi di desa, kepala desa dipilih oleh masyarakat
desa, dan juga ada rembug desa, hal ini lah yang disebut dengan
16 Prof. Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta; Gramedia, 1984), hal. 5017 Agus Sudibyo, “Politik Otentik; manusia dan kebebasan dalam pemikiranHannah Arendt", (Jakarta; Marjin Kiri, 2012), hlm. 32
18
demokrasi asli ala Indonesia. Desa adalah pemula dari demokrasi,
dan sudah saatnya saat ini demokratisasi desa muncul kembali,
melalui demokrasi partisipatif masyarakat desa, yang tidak
terlepas dari 5 ciri yang dari dulu melekat, yakni rapat,
mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama, dan hak
menyingkir dari kekuasaan raja absolut mempergunakan pendekatan
kontekstual.18
Demokrasi adalah nilai dan sistem yang memberi bingkai tata
pemerintahan Desa. Secara konseptual demokrasi mengandung
sejumlah prinsip dasar: representasi, transparansi,
akuntabilitas, responsivitas dan partisipasi, yang semua prinsip
ini menjadi fondasi dasar bagi pengelolaan kebijakan, perencanaan
Desa, pengelolaan keuangan Desa dan pelayanan publik. Kalau
prinsip-prinsip dasar ini tidak ada di Desa, maka akan muncul
“penguasa tunggal” yang otokratis, serta kebijakan dan keuangan
Desa akan berjalan apa adanya secara rutin, atau bisa terjadi
kasus-kasus bermasalah yang merugikan rakyat Desa.
Demokrasi Desa akan membuka ruang bagi rakyat untuk
menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah Desa. Aspirasi adalah
18 Miriam Budiarjo, “Demokrasi di Indonesia, Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila” (Jakarta: Gramedia, 1996)
19
fondasi kedaulatan rakyat yang sudah lama diamanatkan dalam
konstitusi. Demokrasi juga menjadi arena untuk mendidik mental
dan kepribadian rakyat agar mereka lebih mampu, mandiri, militant
dan mempunyai kesadaran tentang pengelolaan barang-barang publik
yang mempengaruhi hidup mereka. Pendidikan dan pembelajaran ini
penting, mengingat masyarakat cenderung pragmatis secara ekonomi
dan konservatif secara politik, akibat dari perkembangan zaman
yang mengutamakan orientasi material.
Lemahnya partisipasi (voice, akses dan kontrol) masyarakat
merupakan sisi lain dari lemahnya praktik demokrasi di tingkat
Desa. Sampai sekarang, elite Desa tidak mempunyai pemahaman yang
memadai tentang partisipasi. Bagi kepala Desa, partisipasi adalah
bentuk dukungan masyarakat terhadap kebijakan pembangunan
pemerintah Desa. Pemerintah Desa memobilisasi gotong-royong dan
swadaya masyarakat (yang keduanya dimasukkan sebagai sumber
penerimaan APBDes) untuk mendukung pembangunan Desa.19
Secara substantif UU No. 5/1979 menempatkan Kepala Desa
bukanlah pemimpin masyarakat Desa, melainkan sebagai kepanjangan
tangan pemerintah supra Desa, yang digunakan untuk mengendalikan
19 Sumber Saparin, “Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa”. (Jakarta: Ghalia, 1977)
20
penduduk dan tanah Desa. UU No. 5/1979 menegaskan bahwa kepala
Desa dipilih oleh rakyat melalui demokrasi langsung. Ketentuan
pemilihan kepala Desa secara langsung itu merupakan sebuah sisi
demokrasi (elektoral) di aras Desa. Di saat presiden, gubernur
dan bupati ditentukan secara oligarkis oleh parlemen, kepala Desa
justru dipilih secara langsung oleh rakyat. Karena itu
keistimewaan di aras Desa ini sering disebut sebagai benteng
demokrasi di level akar-rumput.20
Tetapi secara empirik praktik pemilihan kepala Desa tidak
sepenuhnya mencerminkan kehendak rakyat. Pilkades selalu sarat
dengan rekayasa dan kontrol pemerintah supraDesa melalui
persyaratan yang dirumuskan secara politis dan administratif.
Dalam studinya di Desa-Desa di Pati, Franz Husken (2001)
menunjukkan bahwa pilkades selalu diwarnai dengan intimidasi
terhadap rakyat, manipulasi terhadap hasil, dan dikendalikan
secara ketat oleh negara. Bagi Husken, pilkades yang paling
menonjol adalah sebuah proses politik untuk penyelesaian hubungan
kekuasaan lokal, ketimbang sebagai arena kedaulatan rakyat.
20 Ibid.,
21
Kekurang-sempurnaan demokrasi Desa tidak hanya terlihat dari
sisi pilkades, tetapi juga pada posisi kepala Desa. UU No. 5/1979
menobatkan kepala Desa sebagai “penguasa tunggal” di Desa. Kepala
Desa sebagai kepanjangan tangan birokrasi negara, akibatnya dia
harus mengetahui apa saja yang terjadi di Desa, termasuk
”selembar daun yang jatuh dari pohon di wilayah yurisdiksinya”.
Akibat selanjutnya, Kepala Desa dalam menjalankan ”perintah”
untuk mengendalikan wilayah dan penduduk Desa terkadang
mengendalikan seluruh hajat hidup orang banyak. Ken Young (1993)
bahkan lebih suka menyebut Kepala Desa sebagai “fungsionaris
negara”
G. METODE PENELITIAN
H. Jenis Penelitian
Metode merupakan cara atau strategi yang digunakan untuk
memperoleh data yang diperlukan. Metode adalah kegiatan ilmiah
yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk
memahami suatu subjek atau objek penelitian sebagai upaya
menemukan jawaban ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun
jenis penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis
22
normatif. Metode penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini
hendak menganalisis Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang
Desa dalam Mewujudkan Kemandirian Pemerintahan Desa Melalui
Penguatan Demokrasi Partisipatif Masyarakat Desa (analisis
normatif Bab XI Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah serta Rancangan Undang-Undang tentang Desa)
I. Pendekatan Penelitian
Berdasarkan penelitian di atas maka saya mengambil
pendekatan penelitian yang di lakukan antara lain; Pertama
pendekatan perundang-undangan (statuta approach), Pendekatan
undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan
regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang
ditangani. Hal ini meliputi peraturan yang berkaitan dengan
Otonomi Daerah serta yang berhubungan dengan desa seperti Undang-
undang dasar 1945 amandemen ke-4 tahun 2002, Undang-Undang nomor
32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan
Pemerintah no 72 tahun 2005 tentang Desa, serta Rancangan Undang-
Undang tentang Desa.
23
Kedua, pendekatan sejarah (Historical Approarch) yaitu
pendekatan sejarah terhadap perkembangan otonomi daerah dan desa
mulai dari zaman colonial, orde lama, zaman orde baru, zaman
reformasi, hingga pasca reformasi,. Pendekatan sejarah di lakukan
untuk mengetahui model otonomi daerah dan pemerintahan desa yang
di anut oleh Indonesia pasca kemerdekaan. Hal ini di lakukan agar
dapat memberikan kecenderungan bagi peneliti untuk merefleksikan
hukum secara lebih mendalam yang berkaitan dengan pemerintahan
desa sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman
maupun penerapan sistem hukum tertentu.
Ketiga, pendekatan konseptual (conseptual approarch). Konsep
dalam pengertian yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang
mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang
kadangkala menunjuk pada hal-hal yang partikular. Pendekatan di
arahkan untuk mengindentifikasi atau menetapkan suatu konsep
tertentu dalam hukum. Hal ini di lakukan dengan cara menganalisis
karakteristik desa dan hakekat desa.
J. Jenis Bahan Hukum
1. Bahan Hukum Primer
24
Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh dari bahan-
bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat.
Bahan-bahan primer terdiri dari;
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
b. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah
c. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa
d. Rancangan Undang-Undang tentang Desa
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak
mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang
merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli
yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan
memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Dalam
penelitian ini bahan hukum sekunder meliputi data sebagai
informasi yang di peroleh dari literatur yang berhubungan dengan
topik yang peneliti angkat, yaitu;
a. Artikel ilmiah
b. Surat kabar
25
c. Studi kepustakaan
d. Dokumen-dokumen yang di dapat melalui internet
e. Hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik
penelitian
3. Bahan Hukum Tersier
a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
b. Kamus Hukum Indonesia
c. Kamus Bahasa Inggris
d. Kamus Filsafat
K. Metode Pengumpulan Bahan Hukum
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer di peroleh melalu studi pustaka terhadap
peraturan tentang pemerintahan yang relevan serta dokumen penting
lainnya.
26
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder di peroleh melalui studi pustaka
terhadap peraturan yang masih berkaitan dengan pemerintahan desa
serta dokumen-dokumen pendukung yang di peroleh dari internet.
c. Bahan Hukum tersier
Bahan hukum tersier diperoleh dengan mengutip langsung
kamus, dan doktrin-doktrin yang berkaitan langsung dengan masalah
yang di angkat peneliti.
L. Teknik Analisis Bahan Hukum
Bahan hukum primer yang telah di kumpulkan di analisis
dengan menggunakan metode yuridis kualitatif yang di gunakan
dalam disiplin ilmu hukum yaitu dengan memperhatikan substansi
yang terkandung dalam undang-undang, sehingga di temukan suatu
pengertian dan kaitan antara bahan hukum primer dengan konsep
pemerintahan desa dalam mewujudkan kemandirian desa melalui
penguatan demokrasi partisipatif masyarakat desa.
Pada bahan hukum sekunder, penulis mengumpulkan data yang di
perlukan untuk kemudian di olah dengan mengkomparasikan atau
27
mengeborasikan dan di jelaskan dengan metode argumentatif
sehingga membentuk suatu wacana terhadap masalah yang di angkat
peneliti. Pada bahan hukum tersier, penulis mengutip dari kamus-
kamus yang di perlukan untuk menjelaskan suatu istilah-istilah
atau doktrin-doktrin tertentu yang berkaitan dengan masalah yang
di angkat peneliti.
M. Definisi Konseptual
1. Otonomi Daerah
Pelimpahan kekuasaan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan
provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana yang diamanatkan oleh
undang-undang, termasuk hak, wewenang, dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
2. Desa
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
28
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Demokrasi Partisipatif
Demokrasi partisipatif adalah sebuah proses demokrasi yang
menekankan partisipasi luas dari konstituen atau rakyat dalam
arah dan pengoperasian sistem politik termasuk didalamnya dalam
hal keputusan dan kebijakan dari pemerintah. Berbeda dengan
demokrasi perwakilan tradisional yang cenderung membatasi
partisipasi warga untuk memberikan suara, dan meninggalkan
pemerintahan yang sebenarnya kepada para politisi.
29