pemetaan karakteristik tanah gambut di - Repository Unja
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of pemetaan karakteristik tanah gambut di - Repository Unja
PEMETAAN KARAKTERISTIK TANAH GAMBUT DI
WILAYAH KANAL PANGGULONAN PANJANG
DESASEPONJENKECAMATAN KUMPEH
KABUPATEN MUARO JAMBI
IYUT MARETA FITRAH
PROGRAM STUDI TEKNIK PERTANIAN
JURUSAN TEKNOLOGI PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS JAMBI
2021
PEMETAAN KARAKTERISTIK TANAH GAMBUT DI
WILAYAH KANAL PANGGULONAN PANJANG
DESA SEPONJEN KECAMATAN KUMPEH
KABUPATEN MUARO JAMBI
IYUT MARETA FITRAH
J1B115001
Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Teknologi Pertanian
PROGRAM STUDI TEKNIK PERTANIAN
JURUSAN TEKNOLOGI PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS JAMBI
2021
PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawahini:
Nama : Iyut Mareta Fitrah
Nim : J1B115001
Jurusan : Teknik Pertanian
Judul Skripsi : Pemetaan Karakteristik Tanah Gambut di Wilayah Kanal
Panggulonan Panjang Desa Seponjen Kecamatan Kumpeh
Kabupaten Muaro Jambi
Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Skripsi ini merupakan karya asli penulis tersebut di atas dan belum
pernah diajukan atau tidak dalam proses pengajuan dimanapun.
2. Sumber kepustakaan dan bantuan dari berbagai pihak yang diterima
selama penelitian dan penyusunan skripsi ini telah
dicantumkan/dinyatakan pada bagian yang relevan.
3. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar saya
bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku. Atau Apabila di
kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini telah diajukan atau dalam
proses pengajuan oleh pihak lain dan/atau terdapat plagiarisme di
dalam skripsi ini, maka saya bersedia dituntut sesuai pasal 12 ayat 1
butir g Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.17 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi,
yakni pembatalanijazah.
Jambi, Juli 2021
Penulis
Iyut Mareta FItrah
J1B115001
4
HALAMAN PENGESAHAN
PEMETAAN KARAKTERISTIK TANAH GAMBUT DI
WILAYAH KANAL PANGGULONAN PANJANG
DESA SEPONJENKECAMATAN KUMPEH
KABUPATEN MUARO JAMBI
IYUT MARETA FITRAH
J1B115001
PROPOSAL SKRIPSI
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
di Program Studi Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian
Universitas Jambi
Menyetujui
Pembimbing I
Pembimbing II
Dr. Ir. Aswandi., M.Si
NIP.196212271990011001
Nur Hasnah AR, S.TP., M.Si
NUP. 9900008919
Mengesahkan,
Ketua Jurusan Teknologi Pertanian
Fakultas Pertanian Universitas Jambi
Dr.Ir. Sahrial, M.Si
NIP.196611031992031005
09 Juli 2021
5
Iyut Mareta Fitrah. J1B115001. Pemetaan Karakteristik Tanah Gambut Di
Wilayah Kanal Panggulonan Panjang Desa Seponjen Kecamatan Kumpeh
Kabupaten Muaro Jambi. Pembimbing : Dr.Ir.Aswandi., M.Si dan Nur
Hasnah AR, S.TP., M.Si.
RINGKASAN
Tanah gambut memiliki berbagai keunggulan diantaranya kapasitas menahan air
dan udara yang tinggi persatuan volumenya dibandingkan dengan tanah mineral, struktur
yang remah memungkinkan pertumbuhan akar lebih cepat, bebas dari batuan di samping
itu gambut juga memilki kelemahan yaitu pH gambut yang rendah, kandungan unsur hara
yang relatif rendahdan sulitnya gambut basah kembali. Pemanfaatan lahan gambut
mendapat perhatian besar terutama untuk budidaya tanaman perkebunan. Desa Seponjen
merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kumpeh Muaro Jambi, dimana
penduduknya sebagian besar berprofesi sebagai petani yang memfaatkan lahan gambut
sebagai lahan pertanian yang tersebar hampir seluruh wilayah Desa. Namun, pemanfaatan
lahan gambut di Desa Seponjen belum dilakukan secara maksimal karena kurangnya
informasi dan pengetahuan warga Seponjen atas potensi sumber daya yang terdapat di
desanya. Untuk itu salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan
menganalisis karakteristik tanah gambut agar masyarakat sekitar bisa memanfaatkan
lahan tersebut dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan. Tujuan dari penelitian ini
yaitu untuk mengetahui sifat fisik dan kimiatanah gambut di Wilayah Kanal Panggulonan
Panjang Desa Seponjen Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi.
Penelitian dilakukan dengan pengambilan sampel pada titik yang telah ditetapkan
dengan metode grid (titik pengamatan). Titik pengamatan berdasarkan jalur transek tegal
lurus dengan tanggul sungai atau arah kontur dengan jarak titik pengamatan adalah 200 X
200 cm. Selanjutnya dilakukan uji analisis di lapangan dengan pengukuran pH,
kematangan gambut dan ketebalan gambut (cm) dengan pengeboran langsung dilapangan.
Sedangkan uji analisis laboratorium yang diamati yaitu bobot isi (BD) (gr/cm3) dan kadar
air (%) menggunakan metode gravimetrik, uji C-organik, KTK (kapasitas tukar kation),
dan N-total.
Hasil penelitian yang diamati dilapangan bahwa ketebalan gambut >3 m,
kematangan gambut lapiran permukaan (0-60cm) dominan yaitu kematangan saprik
terdapat pada lahan kelapa sawit dan semak belukar. Hasil penelitian yang diamati
dilaboratorium bahwa nilai bobot volume relatif tinggi (0,2892 g/cm3 , C-organik (52,
38-55, 79%), dan kadar air pada tiap penggunaan lahan tergantung pada tingkat
kematangan lapisan permukaannya di mana mendapatkan nilai sebesar (640%). Semakin
matang gambut maka nilai bobot isi akan semakin tinggi, nilai C-organik, N-total
semkain rendah dan kadar air juga semakin rendah. Begitu pula dengan nilai kemasaman
tanah disebabkan oleh tingginya kandungan asam-asam organik dan ion hydrogen ari
pelapikan bahan organik (3-5). Dan hasil KTK semakin tinggi (62, 32-76, cmol+kg-1)
disebabkan nilai kemasaman yang masih sangat masam. Pada kedalaman gambut besar
dari >300 cm tidak direkomendasikan untuk lahan pertanian ataupun perkebunan
melaiankan direkomendasikan sebagai lahan konservasi.
Kata kunci :Pemetaan, Karakterisik Tanah Gambut, Desa Seponjen
6
RIWAYAT HIDUP
Penulis bernama Iyut Mareta Fitrah, dilahirkan
pada tanggal 15 maret 1997 di Sungai Penuh, Kota
Sungai Penuh, Provinsi Jambi.Penulis merupakan anak
kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak
Azwar Sidin dan Ibu Herlina.Penulis memulai
pendidikan dasar di SD Negeri 98/III Seberang pada
Tahun 2003-2009.Kemudian penulis melanjutkan
pendidikan menengah pertama di SMPN 7 Sungai
Penuh pada Tahun 2009-2012.
Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA N 4
Sungai Penuh pada Tahun 2012-1015. Setelah lulus SMA, penulis melanjutkan
studi ke jenjang Perguruan Tinggi dan diterima di Program Studi Teknik
Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi pada tahun 2015 melalui jalur
SNMPTN.
Selama di perguruan tinggi, penulis pernah bergabung dalam organisasi
kemahasiswaan.Dimulai dari tahun 2015 – 2017 sebagai anggota Himpunan
Mahasiswa Teknik Pertanian (HIMAKTEKTAN). Selain itu, penulis juga pernah
berganung di organisasi IMSL-J (Ikatan Mahasiswa Sungai Liuk – Jambi) san
penulis sebagai sekretaris pada tahun 2015 dan 2017.
Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PTPN6 Unit
Usaha Kayu Aro Jambi-Sumbar pada periode juni hingga agustus 2018 dengan
judul “ Analisa Kerja Mesin Pelayuan Withering Trough Di PT. Perkebunan
Nusantara VI Usaha Kayu Aro”.
Dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi, penulis melakukan penelitian
pada bulan November 2019-februari 2020 dengan judul skripsi “ Pemetaan
Karakteristik Tanah Gambut Di Wilayah Kanal Desa Seponjen Kecamatan
Kumpeh Kabupaten Muro Jmabi” di bawah bimbingan bapak Dr.Ir.Aswandi,
M.,Si dan ibu Nur Hasnah AR, S.TP., M.Si. pada tanggal 9 juli 2021 penulis
melaksanakan ujian skripsi dan dinyatakan lulus sebagai Sarjana Teknik
Pertanian.
7
bissmillahhirohmanirrohim
MOTTO
Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai
penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.
(Q.S Al-Baqarah : 153)
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuanya.
(Q.S Al-Baqarah : 286)
Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang sabar.
(Q.S Al-Anfaal : 46)
Persembahan
Sembah, sujud, dan syukur kepada Allah SWT berkat dan karunia serta kemudahan yang engkau berikan sehingga skripsi ini dapat
kupersembhakan kepada orang-orang yang aku sayangi. tak lupa sholawat beriring salam dihadiahkan pada junjungan alam Nabi besar
Muhammad SAW.
Ku persembahkan karya tulis ini teruntuk :
Abak dan Mak
Yang tidak pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak
tergantikan hingga aku sellau kuat menjalani setiap rintangan dan cobaan yang ada didepanku dan terima kasih selalu bersedia mendengarkan
ceritaku, keluh dan kesahku…teruntuk abak terima lah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu dalam hidupmu
demi hidupku kalianikhlas mengorbankan segala perasaan tanpa kenal lelah…teruntuk mak yang ada di Syurganya Allah SWT kukirimkan kado
kecil ini sebagai hadiah untuk jarak yang begitu jauh ini…maafkan anakmu abak mak yang masih saja selalu menyusahkan abak mak.
Untuk saudara kandungku abang ( eric prananda, S.Pd) dan seluruh Keluargaku yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, senyum dan
doanya untuk keberhasilan ini, terima kasih dan rasa sayangku untuk kalian.
Terima kasih untuk pembimbingku bapak Dr.Ir.Aswandi, M.,Si dan ibu Nur Hasnah AR, S.TP.,M.Si serta Dosen penguji ibu Dr. Eva Achmad, S.Hut.,
M.Sc dan ibu Nurfaijah, S.TP.,M.Si atas bimbingan ilmu semangat dan motivasinya selama perkuliahan maupun selama penyusunan skripsi ini.
8
Selanjutnya teruntuk semua dosen jurusan teknologi pertanian yang telah memberikan pelajaran dan ilmunya.
Untuk Teman Seperjuangan
Team Gambut
Halimah, Feri, Reza, Yogi. Terimakasih untuk cerita, pengalaman, kerja sama dan bantuannnya baik selama penelitian. Semoga sukses untuk kita
semua.
Team PT. Perkebunan NusantaraVI
FriskaHutabarat,IyutMaretaFitrah,EkaPutriUtami,IndahTriUtari,Siti Dina Nursya’adah, Putri Tresia Manurung,Oline Yatinko Tanjung, Avil
Rozendo,SeriMulianti,IndahSartikaTerimaksaihsudahmenjaditaemyang kompak,keseruankaliandankebersamaannyaselamaduabulan.
Queen_Cay Squad FemaSriWahyuni,FentiNadiaFista,HusnulKhotimah,IyutMaretaFitrah,
NonikWidyaFirma,Sriyuna,WaraDetriHanipaTerimakasihTelahmenjadi sahabat dan keluargaku selama diperantauan ini, berbagi suka duka
bersama.
Sahabat-sahabat Seperjuangan TEP 2015
Aan, masitah, hindun,juli, elwena, siska S, asma, alwin, wahyu, eikel, yenni, ani, aris, shirly, clara, atun, nisa, bernardo, diah, desy, cindy, pebri,
estrekita, enjel, panro, tomi, fachrian, randa, ilham, dabanus, addre, rizki, reza, abi, yusuf, halimah, lusita, ratih, rebut, ardianto, andre, krisna, robi,
hasbi, syamsul, yogi, siska L, imam, rega, jimmy, ardi, januar. Terima kasih atas kebaikan, semangat, dan canda tawa suka duka yang sangat
mengesankan selama perkuliahan.
See You on The Top
Keluarga Besar Himaktektan
Terima kasih untuk keluarga besat Himpunan Mahasiswa Teknik Pertanian (HIMAKTEKTAN) Universitas Jambi atas pelajaran, pengalaman, semangat
dan canda tawa yang kalian berikan. Semoga persaudaraan kita tidak luntur karna jarak dan waktu. Semoga kita menjadi orang sukses dan
bermanfaat.
Salam HIMAKTEKTAN !!!
Terakhir, terima kasih untuk semua pihak yang tidak dapat saya cantumkan satu per satu, orang-orang dibalik semua kesuksesan
perjuangan ditahap ini. Terima kaish untuk bantuan, doa, dukungan, dan motivasinya.
i
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena
atas berkat rahmat dan hidayahnya telah membukakan hati dan pikiran penulis,
sehingga dapat menyelesaikan penulisan proposal penelitian yang berjudul
“Pemetaan Karakteristik Tanah Gambut di Wilayah Kanal Panggulonan
Panjang Desa Seponjen Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro
Jambi”dengan baik dan tepat waktu.
Dalam proposal penelitian ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih
kepada seluruh pihak yang telah membantu sehingga proposal penelitian ini dapat
diselesaikan, terutama kepada :
1. Bapak Prof. Dr. Ir. Suandi, M.Si Selaku Dekan Fakultas Pertanian.
2. Bapak Dr. Ir. Sahrial, M.Si selaku Ketua Jurusan Teknologi Pertanian.
3. Ibu Dr. Fitry Tafzi. S.TP, M.Si selaku Ketua Jurusan Teknik Pertanian
sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan
bimbingan, motivasi, dan arahan selama proses perkuliahan.
4. Bapak Dr. Ir. Aswandi, M.Si selaku Pembimbing skripsi I yang telah
membimbing dan memberikan arahan dalam penyempurnaan
penulisan skripsi ini.
5. Ibu Nur Hasnah AR,S. TP.,M.Si selaku dosen pembimbing skripsi II
yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam
penyempurnaan penulisan skripsi ini.
Penulis juga memohon maaf apabila dalam skripsi ini terdapat
kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik sangat penulis harapkan. Semoga
skripsi ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, khususnya bagi penulis
pribadi dan bagi jurusan Teknik Pertanian Universitas Jambi.
Jambi, J2021
Penulis
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................. i
DAFTAR ISI .................................................................................................. ii
DAFTAR TABEL .........................................................................................iii
DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... iv
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................ v
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. 1
1.1 Latar Belakang ......................................................................................... 1
1.2 Tujuan ...................................................................................................... 4
1.3 Hipotesis ................................................................................................... 4
1.4 Manfaat .................................................................................................... 4
BAB II, TINJAUAN PUSTAKA .................................................................. 5
2.1 Tanah Gambut .......................................................................................... 5
2.2 Sifat Fisik Tanah Gambut ....................................................................... 10
2.3 Sifat Kimia Tanah Gambut ..................................................................... 15
BAB III , METODELOGI PENELITIAN ................................................ 21
3.1 Waktu Dan Tempat .................................................................................. 21
3.2 Bahan Dan Alat ....................................................................................... 21
3.3 Metode Penelitian .................................................................................... 21
3.4 Pelaksanaan Penelitian ............................................................................ 22
3.4.1 Tahap Persiapan .............................................................................. 22
3.4.2 Surpey Pendahuluan ........................................................................ 22
3.4.3 Pengamatan ..................................................................................... 22
3.4.4 Pasca Surpei Lapangan .................................................................... 23
3.5 Parameter Yang Diamati ......................................................................... 23
3.6 Analisis Data ........................................................................................... 28
BAB IV , HASIL DAN PEMBAHASAN .................................................. 29
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian ....................................................... 29
4.2 Parameter Yang Diamati ......................................................................... 29
4.2.1 Ketebalan Gambut .......................................................................... 29
4.2.2 Kematangan Gambut ....................................................................... 31
4.2.3 Bobot Isi (BD) & Kadar Air ............................................................. 32
4.2.4 Kemasaman Tanah ......................................................................... 34
4.2.5 C-Organik ........................................................................................ 36
4.2.6 N-Total ............................................................................................ 37
4.2.7 Ktk ( Kapasitas Tukar Kation) ........................................................ 38
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ....................................................... 40
5.1 KESIMPULAN ....................................................................................... 40
5.2 SARAN .................................................................................................. 40
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................. 41
LAMPIRAN ................................................................................................. 45
iii
DAFTARTABEL
Tabel : Halaman
1. Luas Total Lahan Gambut & Yang Layak Untuk Pertanian
Serta Sebarannya ..................................................................................... 6
2. Tabel ketabalan tanah gambut lok. Penelitian ........................................ 30
3. Tingkat kematangan lapisan permukaan ................................................. 32
4. Bobot isi (BD) Tanah gambut dari lapisan 0 smpai 60 cm .................... 34
5. Krtiteria penilaian kemasaman tanah (PH) ............................................ 35
6. C-Organik ............................................................................................... 36
7. Kriteria penilaian N-Total & KTK ( kapasitas tukar kation) ................. 38
iv
DAFTAR GAMBAR
Gambar : Halaman
1. Pembentukan tanah gambut ....................................................................... 8
2. Diagram alir pelaksanaan penelitian...........................................................22
3. Kedalaman Gambut .................................................................................... 31
4. Pengamatan tingkat dekomposisi lampiran Permukaan .......................... 32
5. Kemanagan Gambut ................................................................................... 33
6. Pengematan PH .......................................................................................... 35
v
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran : Halaman
1. Diagram Alir Metode Penelitian ............................................................ 45
2. Peta Administrasi......................................................................................46
3. Peta Lokasi Penelitian ............................................................................ 47
4. Peta Ketebalan Gambut .......................................................................... 48
5. Peta Kematangan Gambut ...................................................................... 49
6. Kriteria Tingkat Dekomposisi Bahan Organik Menurut
Metode Perasvanpos ............................................................................... 50
7. Hasil Analisis N- Total & Ktk ................................................................ 51
8. Hasil Pengematan Kemasaman Tanah ................................................... 52
9. Bobot Isi (BD) & Kadar Air Tanah ........................................................ 53
10. C-Organik ............................................................................................... 64
11. Dokumentasi Penelitian .......................................................................... 74
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Indonesia memiliki lahan gambut terluas di antara negara tropis, yaitu
sekitar 14,91juta ha. Upaya pemanfaatan lahan gambut yang yang paling
menonjol saat ini adalah alih fungsi lahan gambut untuk HTI (Hutan Tanaman
Industri) dan perkebunan kelapa sawit (Widyati, 2011). Perkebunan kelapa sawit
paling luas berada di Sumatera (69,1% dari luas kebun kelapa sawit di Indonesia)
terutama di Provinsi Riau, Sumatera Utara, dan Sumatera selatan serta Kalimantan
(Wahyunto et al., 2013).
Lahan gambut merupakan lahan hasil akumulasi timbunan bahan organik
yang berasal dari pelapukan vegetasi yang tumbuh disekitarnya dan terbentuk
secara alami dalam jangka waktu yang lama. Tanah gambut adalah tanah yang
memiliki kandungan utama berupa bahan organik yang tinggi yang berasal dari
sisa-sisa jaringan tanaman. Gambut memiliki berbagai keunggulan, diantaranya
kapasitas menahan air dan udara yang tinggi persatuan volume dibandingkan
dengan tanah mineral, struktur yang remah yang memungkinkan pertumbuhan
akar lebih cepat, bebas dari batuan/kerikil yang dapat memungkinkan kualitas
tanah lebih baik dan ringan (bobot isi rendah). Di samping itu, gambut juga
memiliki beberapa kelemahan bila digunakan sebagai media tumbuh tanaman,
yaitu pH gambut yang sangat rendah, kandungan unsur haranya relatif rendah, dan
sulitnya gambut basah kembali setelah mengalami kekeringan. Dalam usaha
perbaikan sifat fisik dan kimia gambut untuk media tumbuh diperlukan
penambahan unsur Ca (Kalsium) dan Mg (Magnesium), khususnya untuk
meningkatkan pH dan persen kejenuhan basa (satari, 1988). Menurut Madiapura,
Amir dan Zulfahmi (1977, dalam soepardi, 1983), dua buah kation yang paling
cocok untuk mengurangi kemasaman tanah, ialah Kalsium dan Magnesium.
Kedua kation tersebut mudah dijumpai di alam dalam jumlah banyak dan
memberikan efek menguntungkan terhadap sifat fisik tanah.
Pemanfaatan lahan gambut mendapat perhatian besar, terutama untuk
budidaya tanaman perkebunan. Selain itu, lahan gambut juga berpotensi besar
untuk budidaya tanaman pangan (Utama dan Haryoko, 2009). Sedangkan menurut
2
Sagiman (2007) pengembangan lahan gambut untuk pertanian tidak hanya
ditentukan sifat-sifat fisik maupun kimia gambut, namun dipengaruhi pula oleh
manajemen usaha tani yang akan diterapkan. Sifat fisik tanah merupakan kunci
penentu kualitas suatu lahan dan lingkungan. Lahan dengan sifat fisika yang baik
akan memberikan kualitas lingkungan yang baik juga. Sifat kimia tanah diambil
sebagai pertimbangan pertama dalam menetapkan suatu lahan untuk pertanian
(Yulnafatmawati et al., 2007). Sifat fisika tanah gambut merupakan bagian dari
morfologi tanah yang penting peranannya dalam penyediaan sarana tumbuh
tanaman (Suswati et al., 2011).
Menurut penelitian Arminudin et al., (2015) hasil terbaik pada analisis sifat
fisik tanah gambut provinsi Riau pada kedalaman 0-50 cm dan 50-100 cm
tergolong gambut hemik dengan kadar serat masing-masing 41% dan 61%,
sedangkan kedalaman 100-150 cm tergolong gambut fibrik kadar serat yang
didapatkan 70,25%. Sedangkan pada penelitian Dikas (2010) untuk karakteristik
fisik gambut di Riau pada fisiografis hutan sekunder hasil terbaik untuk kadar
serat di dapatkan pada kedalaman 120-250 cm yakni 70% dan kedalaman 250-350
cm kadar serat yang didapatkan adalah 80%. Identifikasi sifat fisik lahan gambut
untuk pengembangan jagung, tanah saprik didapat pada ketebalan gambut 50-100
cm dan pada kedalaman 54-120 cm menghasilkan warna coklat gelap (Indradewa
et al., 2011).
Menurut Nugroho et al. (2013) konversi hutan gambut sekunder menjadi
perkebunan kelapa sawit menyebabkan perubahan sifat kimia tanah gambut
dengan peningkatan pH (1,19%),penurunanC-organik (17,94%),N-total
(0,23%),Mg-dd (62,54%) dan Na-dd (0,13%), serta dengan ditandai peningkatan
pada kelapa sawit usia 6 tahun dan penurun pada kelapa sawit usia 26tahun
untuk KTK sebesar (11,87% dan 3.44%), K-dd (0,05% dan 0,09%) dan Ca-dd
(13,89 dan 63,2%).
Keberadaan lahan gambut saat ini semakin terancam karena mendapat
tekanan dari berbagai aktivitas manusia. Pengembangan lahan gambut saat ini
dimanfaatkan untuk komoditi tanaman tahunan( pertanian atau perkebunan dan
hutan tanaman industri). Pemanfaatan lahan gambut untuk pertanian pangan
ataupun perkebunan tergolong sangat rawan, terutama jika dilaksanakan pada
3
gambut tebal di daerah pedalaman ( gambut dalam) akan berdampak buruk ada
lahan gambut itu sendiri (Limin, 2006). Sesungguhnya, lahan-lahan gambut
terutama di Indonesia telah sejak lama diusahakan sebagai lahan pertanian oleh
penduduk lokal dan belakangan ini semakin banyak pula lahan gambut yang
dibuka untuk budidaya tanamana pangan, holtikultura, dan perkebunan. Namun
demikian, keberhasilan budidaya tanaman pada lahan-lahan gmabut tersebut
masih sangat beragam dan rata-rata masih rendah karena terdapatnya berbagai
kendala yang belum sepenuhnya dapat diatasi termasuk yang bersifat bawaan
(inherent) maupun yang bersumber dari konversi lahan gambut (Radjagukguk B,
2000).
Salah satu daerah yang memanfaatkan lahan gambut sebagai kawasan
pertanian adalah Desa Seponjen yang terletak di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten
Muaro Jambi. Dimana penduduknyasebagian besar berprofesi sebagai petani yang
memanfaatkan lahan gambut yang tersebar hampir seluruh wilayah desa. Akan
tetapi, sebagian lahan yang dimanfaatkan tersebut berada pada wilayah gambut
sangat dalam (>300cm) yang tergolong kedalam wilayah konservasi dan terdapat
juga di beberapa lahan yang di drainase atau dilakukan pembuatan kanal sehingga
akan berdampak pada beberapa sifat fisik dan kimia yang ada pada lahan tersebut.
Menurut Furukawa (2003) sistem kanal yang terbuka lebar, dalam dan panjang
telah memberikan dampak negatif terhadap lahan gambut yang tereklamasi karena
yang pertama kanal-kanal yang dalam telah mempercepat proses pengeringan
lahan, mempercepat proses dekomposisi lapisan gambut dan pengeluaran sulfur
dalam jumlah yang sangat besar. Yang kedua, kanal yang panjang mempengaruhi
arus air dalam kanal dengan gradien hidrolik yang rendah, sehingga
memperlambat arus air dan membuat prosespencucian bahan-bahan berbahaya
yang terdapat di air oleh air tawar yang baru terhambat. Kemudian yang ketiga,
kanal terbuka akan memperburuk proses lebih lanjut pada saat pasang tinggi arus
air yang masuk saling menganggu sehingga aliranair baik mengalami gangguan,
sedangkan pada saat pasang rendah maka akan terjadi pendrainasean air dari dua
sisi ujung kanal, sehingga menyebabkan penurunan yang cepat gradien hidraulis
yang mana dapat mengurang efektivitas aliran air balik ke kanal.
4
Tanah gambut di Desa Seponjen merupakan jenis tanah yang topogen.
Dengan demikian, tanah gambut di Desa Seponjen secara tidak langsung akan
dipengaruhi oleh luapan banjir dari sungai yang mengakibatkan terjadinya
degradasi pada lapisan permukaan tanah gambut. Berdasarkan uraian diatas maka
penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ Pemetaan Karakteristik
Tanah Gambut di Wilayah Kanal Panggulonan Panjang Desa Seponjen
Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi “
1.2 Tujuan
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sifat fisik dan
kimiatanah gambut di Wilayah Kanal Panggulonan Panjang Desa Seponjen
Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi.
1.3 Hipotesis
Hipotesis dari penelitian ini adalah sifat fisik dan kimia tanah gambut
berpengaruh terhadap kualitas tanah di Wilayah Kanal Panggulonan Panjang Desa
Seponjen Kabupaten Muaro Jambi.
1.4 Manfaat
Dengan dilakukannya penelitian ini dapat diketahui sifat sifik, kimia tanah
gambut di kawasan sungai panggulonan panjang sehingga dapat di manfaatkan
oleh penduduk sekitar wilayah di Desa Seponjen Kecamatan Kumpeh Kabupaten
Muaro Jambi.
5
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tanah Gambut
Tanah gambut banyak istilahdalam bahasa inggris, antara lain disebut peat,
bog, moor, mire atau fen. Istilah-istilah ini berkenaan dengan perbedaan jenis atau
sifat gambut antara satu tempat ke tempat lainnya. Gambut diartikan sebagai
material atau bahan organik yaag tertimbun secara alami dalam keadaan basah
berlebihan, bersifat tidak mampat dan tidak atau hanya sedikit mengalami
perombakan (Noor, 2001).
Menurut Andriesse (1992) dalam Noor (2001), gambut adalah tanah
organik (organic soils). Tetapi tidak berarti bahwa tanah organik adalah gambut.
Tanah gambut yang telah mengalami perombakan secara sempurna sehingga
bagian tumbuhan aslinya tidak dikenali lagi dan kandungan mineralnya tinggi
disebut tanah bergambut (muck, peaty, muck, mucky). Tanah organik (gambut)
merupakan suatu nama umum yang digunakan untuk menunjuk tanah-tanah yang
berkembang pada loka-loka pelenggokan bahan organik dalam takaran melimpah.
Tanah gambut (tanah organik) atau tanah orgonosol adalah tanah yang
berasal dari bahan induk organik seperti dari hutan rawa atau rumput rawa,
dengan ciri dan sifat tidak terjadi difrensiasi horizon secara jelas, ketebalan lebih
dari 0,5 meter, warna coklat hingga kehitaman, tekstur debu lempung, tidak
berstruktur, konsistensi tidak lekat-agak lekat, kandungan organik lebih dari 30%
untuk tanah tekstur lempung dan lebih dari 20% untuk tanah pasir, umumnya
bersifat sangat masam (pH 4,0) dan kandungan unsur hara rendah.
Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian (Ritung et al., 2011),
melakukan updating peta lahan gambut terbitan Wetland Internasional dengan
menggunkan data warisan tanah (legacy soil data), data-data hasil survey dan
pemetaan tanah sampai tahun 2011 serta analisis citra satelit (Landsat TM, ALOS,
SPOT), luas lahan gambut terhitung terhitung 14, 91 jt ha. Data lahan gambut
versi terakhir ini digunkan untuk mendukung pelaksanaan Inpres No. 10 tahun
2011 dan No. 6 tahun 2013, tentang penundaan ijin baru pembukaan hutan
alam/primer dan lahan gambut. Tanah gambut paling luas terdapat di Sumatera,
6
disusul Kalimantan dan Papua. Sumatera penyebaran terluas lahan gambut
terdapat sepanjang pantai timur,yaitu di Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Jambi
dan Aceh. Juga terdapat di dataran sempit pantai barat Sumatera yaitu Kabupaten
Pesisir Selatan, Agam dan Pasaman dan muko-muko (Bengkulu). Di kalimantan,
penyebaran gambut cukup luas terdapat di sepanjang pantai barat wilayah
Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Mempawah, Ketapang,
Sambas, Kubu Raya, dan Pontianak. Di papua, penyebaran gambut cukup luas
terdapat di sepanjang daratanpantai selatan sekitar Kota Agats.
Tabel 1. Luas Total Lahan Gambut dan yang Layak untuk Pertanian Serta
Sebarannya di Indonesia
Provinsi/ Pulau Luas (Ha) Luas (%)
Aceh 215.704 3,35
Sumatera Utara 261.234 4,06
Sumatera Barat 100.687 1,56
Riau 3.867.413 60,08
Kepulauan Riau 8.186 0,13
Jambi 621.089 9,65
Bengkulu 8.052 0,13
Sumatera Selatan 1.262.385 19,61
Kep. Bangka Belitung 42.568 0,66
Lampung 49.331 0,77
Sumatera 6.436.649 100
Kalimantan Barat 1.680.135 35,16
Kalimantan Tengah 2.659.234 55,66
Kalimantan Selatan 106.271 2,22
Kalimantan Timur 332.265 6,96
Kalimantan 4.777.905 100
Papua 2.644.438 71,65
Papua Barat 1.046.483 28,35
Papua 3.690.921 100
Luas Total 14.905.475
Sumber : Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian (Ritung et al., 2011)
2.1.1 Pembentukan Tanah Gambut di Indonesia
Pembentukan gambut di beberapa daerah pantai Indonesia di perkirakan
dimulai sejak zaman glasial akhir sekitar 3.000-5.000 tahun yang lalu, sedangkan
7
proses pembentukan gambut pedalaman sekitar lebih lama, sekitar 10.000 tahun
yang lalu (Wahyunto, 2005).
Seperti gambut tropis lainya, gambut di Indonesia dibentuk oleh akumulasi
residu vegetasi tropis yang kaya kandungan lignim dan selulosa. Akibat
lambatnya proses dekomposisi, ekosistem rawa gambut masih dapat dijumpai
batang, cabang, dan akar tumbuhan yang besar. Secara umum, pembentukan dan
pematangan gambut berjalan melalui tiga proses yaitu pematangan fisik,
pematangan kimia, dan pematangan biologi. Kecepatan proses pematangan
tersebut dipengaruhi oleh iklim (suhu dan curah hujan), susunan bahan organik,
aktivitas organisme, dan waktu (Andriesse, 1988). Pematangan gambut melalui
proses pematangan fisik terjadi dengan adanya pelepasan air karena drainase,
evaporasi, dan dihisap oleh akar. Proses ini ditandai dengan penurunan dan
perubahan warna tanah, sedangkan pematangan kimia terjadi melalui peruraian
bahan-bahan organik menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Proses
pematangan ini akan melepaskan senyawa-senyawa asam-asam organik yang
beracun bagi tanaman dan membuat suasana tanah menjadi asam. Gambut yang
telah mengalami kematangan kimia secara sempurna akhirnya akan membentuk
bahan organik baru yang disebut sebagai humus. Terakhir adalah kematangan
biologi adalah proses yang disebabkan oleh aktifitas mikroorganisme tanah.
Proses ini biasanya akan lebih cepat terjadi setelah pembuatan saluran drainase
karena terjadinya oksigen yang cukup menguntungkan bagi pertumbuhan
mikroorganisme.
Proses pembentukan gambut dimulai dari adanya danau dangkal yang
secara perlahan ditumbuhi oleh tanaman air dan vegetasi lahan basah. Tanaman
yang mati dan melapuk secara bertahap membentuk lapisan yang kemudian
menjadi lapisan transisi antara lapisan gambut dengan lapisan dibawahnya berupa
tanah mineral. Selanjutnya, tanaman tumbuh pada bagian yang lebih tengah dari
danau dangkal dan membentuk lapisan-lapisan gambut sehingga danau tersebut
menjadi penuh (Agus dan Subsika, 2008). Proses pembentukan tanah gambut
dapat dilihat pada Gambar 1.
8
Sumber:Darmatin.Proses Pembentukan Lahan Gambut.[1]
Gambar 1. Pembentukan Tanah Gambut
Menurut Driessen (1978) pembentukan tanah gambut terjadi dibawah
kondisi jenuh air seperti pada daerah depresi, danau atau pantai yang banyak
menghasilkan bahan organik yang melimpah oleh vegetasi yang telah beradaptasi
seperti mangrove, rumput-rumputan atau hutan rawa. Pada daerah depresi tersebut
terjadi genangan air terutama dari luapan air sungai dan air hujan. Akibat dari
penggenangan ini, maka proses dekomposisi bahan organik berjalan lambat dan
terjadilah penimbunan bahan organik. Selama penimbunan bahan organik,
komposisi vegetasi berubah secara bertahap sampai akhir terbentuk gambut yang
berkembang dibawah pengaruh air tanah gambut topogen atau gambut air tanah.
Jika curah hujan cukup tinggi, keadaan yang sangat basah pada tanah
gambut tetap terjaga, dengan demikian pelapukan bahan organik menjadi
terhambat dan penimbunan bahan organik berlangsung terus akibatnya permukaan
tanah gambut meningkat dan membentuk gambut yang tebal. Tanah gambut yang
tebal ini dikenal sebagai tanah gambut ombrogen atau gambut air hujan, yaitu
tanah gambut yang pembentukannya hanya dipengaruhi oleh air hujan (Andriesse,
1974; Ismunadji dan Soepardi, 1983). Dengan demikian semakin tebal tanah
gambut, akar tanaman akan sulit mencapai lapisan tanah mineral dibawah tanah
gambut tersebut, dan akhirnya akar-akar tanaman hanya mendapatkan unsur hara
yang berada di lapisan tanah gambut yang semakin miskin tidak mendapat
persediaan hara dari air tanah (Driessen dan Soepraptohardjo, 1974).
2.1.2 Klasifikasi Tanah Gambut
9
Sistem klasifikasi tanah yang sering dijadikan acuan dalam tata nama
tanah-tanah tropik adalah yang dikembangkan oleh Amerika Serikat. Menurut
Soepardi (1983) dalam Iswanto (2005), tanah organik diidentifikasikan sebagai
golongan histosol berdasarkan sistem klasifikasi komprehensif.
Untuk mencegah terjadinya pengklasifikasian kembali setelah tanah
diusahakan tiga faktor yang perlu diperhatikan dalam klasifikasi hitosol
(Hardjowigeno, 1993), yaitu :
a. Kandungan minimum bahan organik.
b. Ketebalan lapisan bahan organik.
c. Kemungkinan terjadinya subsiden bila drainase diperbaiki.
Menurut Noor (2001), jenis gambut dapat dibedakan berdasarkan bahan
asal atau penyusunannya, tingkat kesuburan, wilayah iklim, proses pembentukan,
lingkungan pembentukan, tingkat kematangan dan ketebalan lapisan bahan
organiknya. Sudah tentu terdapat keterkaitan antara bahan asal atau lingkungan
pembentukannya dan tingkat kesuburannya. Demikian juga, ketebalan gambut
berhubungan dengan kematangannya sekaligus dengan tingkat kesuburannya.
Oleh karena itu, gambut yang sama dapat mempunyai lebih dari satu sebutan atau
istilah.
Berdasarkan bahan asal atau penyusunannya, gambut dibedakan menjadi :
a. Gambut lumutan (sedimentairy/sedge peat) adalah gambut yang terdiri
atas campuran tanaman air (family liliceae) termasuk plankton dan
sejenisnya.
b. Gambut seretan (fibrous/sedge peat) adalah gambut yang terdiri atas
campuran tanaman sphagnum dan rumputan.
c. Gambut kayuan (woody peat) adalah gambut yang berasal dari jenis
pohon-pohonan (hutan tiang) beserta tanaman semak (paku-pakuan)
dibawahnya.
Sebagian besar lahan gambut di kawasan tropik Indonesia tergolong
gambut kayuan dan sebagian kecil gambut serat. Gambut seretan yang terdiri atas
tanaman sphagnum umumnya tersebar dikawasan iklim sedang atau dingin dan
10
sebagian dilaporkan terdapat juga dikawasan sub-tropik. Gambut yang berasal
dari kayu-kayuan tergolong oligotrofik/mesotrofik, sedangkan gambut yang
berasal dari serat-seratan tergolong eutrofik.
2.1.3 Karakteristik Gambut
Karakteristik gambut berdasarkan proses awal pembentukannya sangat
ditentukan oleh unsur dan faktor berikut :
a. Jenis tumbuhan (evolusi pertumbuhan flora), seperti lumut (moss), rumput
(herbaceous) dan kayu (wood).
b. Proses humifikasi (suhu/iklim).
c. Lingkungan pengendapan (paleogeografi).
Semua sebaran endapan gambut berada pada kelompok sedimen alluvium
rawa zaman kuater holosen. Lokasi gambut umumnya berada dekat pantai hingga
puluhan kilometer ke pedalaman. Ketebalan maksimum gambut pernah diketahui
mencapai 15 m di Riau (Tjahjono, 2007). Endapan gambut terdapat di atas
permukaan bumi, sehingga endapan gambut dikenal dan dibedakan secara
megaskopis dilapangan. Salah satu cara mengenal endapan gambut secara
megaskopis adalah berdasarkan ciri sifat fisiknya yang sangat lunak menyurupai
tanah, lumpur atau humus yang berasal dari gabungan bagian tumbuhan yang
sudah membusuk seperti daun, batang, ranting dan akar. Tingkat pembusukan
tumbuhan umumnya ditentukan dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan biotik
maupun abiotik. Faktor biotik seperti mikroba tanah yang bersifat anaerob
maupun aerob yang berguna untuk mendekomposisi bahan-bahan organik (lignin,
selulosa, kitin, asam humik, dan lain-lain) menjadi mineral tanah (Yuleli, 2009).
2.2 Sifat Fisik Tanah Gambut
Endapan gambut umumnya berwarna coklat muda hingga coklat tua
sampai gelap kehitaman, sangat lunak, mudah ditusuk, mengotori tangan, bila
diperas mengeluarkan cairan gelap dan meninggalkan ampas sisa tumbuhan yang
didapat dari permukaan bumi hingga beberapa meter tebalnya. Endapan gambut di
permukaan dapat ditumbuhi berbagai spesies tumbuhan mulai dari spesies lumut,
semak hingga pepohonan besar. Gambut yang berwarna lebih gelap biasanya
11
menunjukkan tingkat pembusukan lebih cepat. Secara makroskopis gambut tropis
umunya terdiri atas sisa akar, batang dan daun di dalam jumlah yang berlimpah,
sebaliknya gambut lumut didominasi oleh sisa tumbuhan lumut seperti yang
terdapat di Finlandia (Tjahjono, 2007).
Sifat fisik gambut penting dalam pemanfaatannya untuk pertanian meliputi
kadar air, berat isi (bulk density, BD), daya menahan beban (bearing capacity),
subsiden (penurunan permukaan), dan mengering tidak balik (irreversible drying)
(Agus dan Subsika, 2008). Sifat fisik tanah sangat mempengaruhi pertumbuhan
dan produksi tanaman. Kondisi fisik tanah menentukan penetrasi akar di dalam
tanah, retensi, air, drainase, aerasi dan nutrisi tanaman. Sifat fisik tanah juga
mempengaruhi sifat-sifat kimia dan bilogi (Hakim et al., 1986). Selanjutnya
menurut Hakim et al. (1986), sifat fisik tanah tergantung pada jumlah, ukuran,
bentuk, susunan dan komposisi mineral dari partikel-partikel tanah, macam dan
jumlah bahan organik, volumedan bentuk pori-porinya serta perbandingan air dan
udara menempati pori-pori pada waktu tertentu.
Sifat fisik tanah gambut yang penting dalam pemanfaatannya untuk
pertanian meliputi kadar air, borot isi (bulk density, BD), daya menahan beban,
subsiden (penurunan permukaan tanah), dan mengering tidak balik (irreversible
drying). Kadar air gambut berkisar 100-1300% dari berat keringnya (Mutalib el
al., 1991). Artinya bahwa gambut mampu menyerap air sampai 13 kali bobotnya,
sehingga gambut dapat dikatakan bersifat hidrofilik. Kadar airyang tinggi
menyebabkan BD menjadi rendah, gambut menjadi lembekdan daya menahan
bebannya rendah (Nugroho et al., 1997; Widjaja-Adhi, 1988). Berat isi (BD)
tanah gambut lapisan atas bervariasi antara 0,1-0,2 g/cm3 tergantung pada tingkat
dekomposisinya. Gambut fibrik yang umumnya berada di lapisan bawah memiliki
< dari 0,1 g/cm3, tapi gambut pantai dan gambut di jalur aliran sungai bisa
memiliki BD < 0,2 g/cm3 (Tie and Lim, 1991), karena adanya pengaruh tanah
mineral. Volume gambut akan menyusut bila lahan gambut didrainase, sehingga
terjadi penurunan permukaan tanah (subsiden). Selain karena pemadatan gambut,
subsiden juga terjadi karena adanya proses dekomposisi dan erosi. Dalam 2 tahun
pertama setelah gambut didrainase, laju subsiden bisa mencapai 50 cm/tahun.
12
Pada tahun berikutnya laju subsiden sekitar 2-6 cm/tahun tergantung kematangan
gambut dan kedalaman saluran drainase.
Sifat fisik tanah gambut antara satu dan lainnya saling berhubungan dan
saling memperngaruhi sehingga antara setiap fisik tanah tidak dapat dipisahkan.
Adapun sifat fisik tanah yang penting mencakup yaitu :
a. Kerapatan lindak (bulk density)
Kerapatan lindak (bulk density) merupakan nisbah berat tanah tergregasi
terhadap volumenya, dengan satuan g/cm3 atau g/cc. Kepadatan tanah
mengendalikan kesarangan dan kapasitas sekap air. Bobot isi (bulk
density) merupakan petunjuk tidak langsung arah kepadatan tanahnya,
udara dan air, dan penerobosan akar tumbuhan tanaman ke dalam tubuh
tanah. Keadaan tanah yang padat dapat mengganggu pertumbuhan
tanaman karena akar-akarnya tidak berkembangdengan baik (Baver et
al.,1987 dalam purwowidodo 2005).
Bobot isi tanah dapat bervariasi dari waktu ke waktu dari lapisan ke
lapisan sesuai dengan perubahan ruang pori atau struktur tanah.
Keragaman itu mencerminkan derajat kepadatan tanah. Tanah dengan
ruang pori berkurang dan berat tanah setiap satuan bertambah
menyebabkan meningkatnya bobot isi tanah. Tanah yang mempunyai
bobot besar akan sulit meneruskan air atau sukar di tembus akar tanaman,
sebaliknya tanah dengan bobot isi rendah, akar tanaman lebih mudah
berkembang (Harjdowigeno, 2003).
Bobot isi tanah menunjukkan perbandingan antara berat tanah kering
dengan volume tanah termasuk volume pori-pori tanah, biasanya
dinyatakan dalam g/cm3 (Hakim et al., 1986). Makin padat suatu tanah
makin tinggi bobot isi tanahnya yang berarti semakin sulit meneruskan air
atau di tembus akar tanaman.
Kerapatan lindak tanah gambut beragam antara 0,01 – 0,20 g/cc,
tergantung pada kematangan bahan organik penyusunnya. Kerapatan
lindak yang rendah dari gambut ini memberikan konsekuensi rendahnya
13
daya tumpu tanah gambut. Makin rendah kematangan gambut (mentah),
maka makin rendah nilai kerapatan lindak.
b. Porositas Tanah
Ruang pori total merupakan volume ruang tanah yang ditempati oleh
udara dan air. Persentase volume pori total disebut porisitas tanah. Pori-
pori tanah dapat dibedakan menjadi pori-pori kasar dan pori-pori halus.
Pori kasar berisi udara atau air gravitasi, sedangkan pori halus berisi air
atau kapiler atau udara. Tanah berpasir mempunyai pori-pori kasar banyak
dibandingkan tanah liat. Tanah dengan banyak pori-pori kasar sulit
menahan air sehingga tanaman mudah kekeringan. Tanah liat mempunyai
pori total lebih tinggi dibandingkan tanah berpasir. Porisitas tanah
dipengaruhi oleh kandungan bahan organik, struktur tanahdan tekstur
tanah. Porisitas tanah tinggi jika bahan organiknya tinggi. Tanah dengan
struktur remah atau granuler mempunyai porositas tanah yang lebih tinggi
dari pada tanah-tanah dengan struktur pejal (Hardjowigeno, 2005).
c. Permeabilitas Tanah
Permeabilitas merupakan kecepatan bergeraknya suatu cairan pada
suatu media dengan keadaan jenuh. Permeabilitas ini sangat penting
perannya dalam pengelolaan tanah dan air (Haridjaja 1983 dalam Sianturi
2006). Selanjutnya Russel (1956) menyatakan bahwa permeabilitas tanah
sebagai kecepatan air melalui tanah dalam keadaan jenuh pada periode
tertentu dan dinyatakan dalam cm/jam. Permeabilitas merupakan sifat fisik
yang langsung dipengaruhi oleh pengelolaan tanah (Baver 1961 dalam
Sianturi 2006).
Faktor yang mempengaruhi permeabilitas tanah diantaranya adalah
tekstur, porositas tanah serta distribusi ukuran pori, stabilitas agregat,
struktur tanah dan kandungan bahan organik (Hillel 1980 dalam Sianturi
2006). Menurut Noor (2001), besar permeabilitas tanah gambut ditentukan
oleh jenis gambut, tingkat kematangan gambut, kerapatan lindak dan jeluk.
Makin tinggi laju permeabilitas maka makin mentah gambut (gambut pada
kedalaman< 2 m tergolong fibrik).
14
d. Air Tersedia
Air tanah merupakan sebagian fase cair tanah yang mengisi sebagian
atau seluruh ruang pori tanah. Air tanah berperan penting dari segi
pedogenesis maupun dalam hubunganya dengan pertumbuhan tanaman.
Pertukaran kation, dekomposisi bahan organik, pelarut unsur hara dan
kegiatan jasad-jasad mikro hanya akan berlangsung dengan baik apabila
tersedia air dan udara yang cukup (Haridjaja et al., 1983).
Diantara tanah yang berpengaruh terhadap jumlah air yang tersedia
adalah daya hisap (matrik dan osmotic), kedalaman tanah dan pelapisan
tanah. Daya hisap matrik/partikel tanah sangat jelas mempengaruhi jumlah
air tersedia. Faktor faktos yang berpengaruh terhadap daya menahan air
pada kapasitas lapang dan be juga terhadap daya menahan air yang
tersedia. Faktor-faktor tersebut antaralain tekstur, struktur dan bahan
organik (Hakim et al., 1986).
Kemampuan menyerap dan memegang air dari gambut tergantung
pada tingkat kematangannya. Kemampuan gambut dalam memegang air
mempunyai arti penting bagi pengelolaan lahan gambut. Nilai pegang air
dinyatakan dalam berbagai satuan, antara lain dalam % volume, % bobot
kering atau % bobot basah. Kadar lengas tanah gambut jauh lebih besar
dibandingkan dengan tanah mineral . kadar lengas gambut yang belum
mengalami perombakan berkisar 500% - 1000% bobot, sedangkan yang
telah mengalami perombakan berkisar 200% - 600% bobot (Boelter,
1969).
e. Tekstur Tanah
Tekstur tanah adalah perbandingan nisbi aneka kelompok ukuran
jarak/pisahan tanah yang menyusun massa tanah suatu bagian tubuh tanah.
Pisahan tanah yang digunakan memberikan tekstur adalah : pasir, yaitu
jarak-jarak tanah dengan ukuran Ø 0,2 – 2,0 mm, debu yaitu jarak-jarak
tanah dengan ukuran Ø0,002 – 0,2 mm dan lempung yaitu jarak-jarak
tanah dengan ukuran Ø0,02 mm. Tubuh tanah yang telah berkembang
memperlihatkan perbedaan teksturantar horizon penyusunannya dan
15
perbedaan tersebut dinyatakan dalam bahasa kelas tekstur tanah
(Purwowidodo, 2005).
Tanah disusun oleh partikel yang mempunyai bentuk dan ukuran
yang beragam. Tekstur tanah adalah kehalusan atau kekasaran bahan tanah
pada perabaan berkenaan dengan perbandingan berat antar fraksi tanah.
Dalam hal ini fraksi lempung lebih unggul dibandingkan dengan fraksi
debu dan pasir, tanah dikatakan berstruktur halus dan lempungan sehingga
bersifat berat diolah karena sangat liat dan lekat sewaktu basah dankeras
sewaktu kering, tanah yang unggul seperti fraksi lempung juga disebut
berstruktur berat. Sedangkan tanah yang fraksi pasir disebut kasar, pasiran
atau ringan (mudah diolah, karena longgar dan gembur)
(Notohhardiprawiro, 1999).
Arsyad (2000) mengemukakan bahwa struktur tanah yang penting
dalam mempengaruhi infiltrasi adalah ukuran pori dan kemantapan pori.
Pori-pori yang mempunyai diameter besar (0,06 mm atau lebih)
memungkinkan air keluar dengan cepat sehingga tanah teraerasi baik, pori-
pori tersebut juga memungkinkan udara keluar dari tanah sehingga air
dapat masuk.
Tanah-tanah yang berstruktur halus mempunyai luas permukaan
yang kecil sehingga sulit menyerap dan menahan air atau unsur. Tanah-
tanah yang berstruktur liat mempunyai luas permukaan yang besar
sehingga kemampuan menahan dan menyimpan unsur hara tinggi
(Hardjowigeno, 2003).
2.3 Sifat Kimia Tanah Gambut
Sifat kimia tanah merupakan semua peristiwa yang bersifat kimia yang
terjadi pada tanah, baik pada permukaan maupun dalamnya. Rentetan peristiwa
kimia inilah yang akan yang akan menentukan ciri dan sifat tanah yang akan
terbentuk atau berkembang (Hakim et al., 1986).
Susunan kimia dan kesuburan tanah gambut ditentukan oleh ketebalan
lapisan gambut dalam proses pembentukan dan pematangannya (Widjaya, 1986).
Sifat kimia tanah gambut dicirikan dengan nilai pH dan ketersediaan
16
unsurnitrogen, fosfor dan kalium rendah, kejenuhan kalsium dan magnesium
rendah, diikuti dengan pertukaran Al, Fe, Mg yang cukup tinggi sehingga akan
mempengaruhi pertumbuhan tanaman (Hakim et al., 1986).
Menurut Saharjo et al. (2000) kondisi tanah setelah terbakar menunjukkan
pH dan P akan naik, C-organik dan NH4+ akan turun, NO3
- tanah tetap dan kadar
abu akan naik, semua faktor yang disebutkan dapat meningkatkan pertumbuhan
tanaman dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang kondisi tanah akan
kembali pada kondisi yang tidak menunjang bagi pertumbuhan tanaman.
Sifat kimia lahan gambut di Indonesia sangat ditentukan oleh kandungan
mineral, ketebalan. Jenis mineral pada sub stratum (didasar gambut), dan tingkat
dekomposisi gambut. Kandungan mineral gambut di Indonesia umumnya kurang
dari 5% dan sisanya adalah bahan organik. Fraksi organik terdiri dari senyawa-
senyawa humat sekitar 10-20% dan sebagian besar lainnya adalah senyawa lignin,
selulosa, hemiselulosa, lilin, tannin, resin, suberin, protein, dan senyawa lainnya
(Agus dan Subsika, 2008).
Kesuburan alamiah tanah gambut dapat berbeda antara satu dan lainya
diakibatkan adanya perbedaan ketebalan lapisan gambut, tingkat dekomposisi,
komposisi tanaman penyusun gambut serta lapisan tanah mineral yang berada
dibawahnya. Secara kimiawi, tanah gambut umunya bereaksi masam dengan pH
3-4,5. Gambut dangkal umumnya memiliki pH lebih tinggi (pH 4-5,1) dari pada
gambut dalam (pH 3,1-3,9). Kandungan N total pada tanah gambut termasuk
tinnggi namun kurang tersedia bagi tanaman karena nisbah C/N yang tinggi.
Kadar abu merupakan petunjuk yang tepat untuk mengetahui tingkat keseburan
alami gambut. Pada umunya gambut dangkal yang terdapat pada tepi kubah
memiliki kadar abu sekitar 15%, bagian lereng dengan kedalaman 1-3 meter
berkadar sekitar 10% dan kubah yang lebih tebal dari 3 meter berkadar kurang
dari 10% bahkan hingga kurang dari 5%. Kapasitas tukar kation tanah gambut
umunya sangat tinggi (90-200me/100g) tetapi kejenuhan basa sangat rendah
(BBSDLP, 2008).
17
Adapun sifat kimia tanah yang terpenting mencakup :
a. Kemasaman Tanah (pH)
Keasaman tanah (pH) adalah suatu parameter penunjuk keaktifan
ion-ion H+ dalam larutan tanah. Ion-ion tersebut berkeseimbangan dengan
H tidak terdisosiasi senyawa-senyawa dapat larut dan tidak dapat larut
yang terdapat dalam sistem tanah itu. Nilai pHmenunjukkan intensitas ion-
ion H+ terdisosiasi dan tidak terdisosiasi disebut kapasitas kemasaman
tanah. Nilai pH tanah-tanah masam terutama dikendalikan oleh ion-ion
H+, Al3+ dan Fe3
+ dalam larutan dan komplek jerapan sedangkan pada
tanah-tanah netral atau alkalis dikendalikan terutama oleh ion-ion Ca2+
dalam larutan dan komplek jerapan. Cara ion-ion itu mengendalikan pH
adalah berbeda-beda, yang berkaitan dengan perbedaan sumber dan watak
muatan negatif yang disandangnya (Purwowidodo 2005).
Sumber keasaman atau yang berperan dalam menentukan keasaman
pada tanah gambut adalah pirit (senyawa sulfur) dan asam-asam organik.
Tingkat keasaman tanah gambut mempunyai kisaran sangat lebar.
Umumnya tanah gambut tropik, terutama gambut ombrogen (oligotrofik),
mempunyai kisaran pH 3,0 – 4,5, kecuali yang mendapatkan pengaruh
penyusupan air laut atau payau. Keasaman tanah cenderung makin tinggi
jikagambut tersebut makin tebal (Noor,2001).
b. Bahan Organik
Pengaruh bahan organik terhadap sifat-sifat tanah dan akibatnya
terhadap pertumbuhan tanaman adalah sebagai granulator yaitu
memperbaiki struktur tanah, sumber hara, unsur hara N, P,S, unsur mikro,
menambah kemampuan tanah untuk menahan air, menambah kemampuan
tanah untuk menahan unsur-unsur hara dan sumber energi bagi
mikroorganisme. Bahan organik umumnya ditemukan di permukaan tanah,
jumlahnya tidak besar hanya 3 – 5 % saja tetapi pengaruhnya terhadap
sifat-sifat tanah sangat besar (Hardjowigeno 2003).
c. Kapasitas Tukar Kation
Kapasitas Tukar Kation (KTK) pada tanah gambut lebih besar
dibandingkan tanah mineral. Nilai KTK memegang peranan penting dalam
18
pengelolaan tanah dan dapat menjadiciri kesuburan tanah. KTK tanah pada
jumlah muatan negatif yang berada pada kontak jerapan (Hardjowegeno
1989).
KTK tanah gambut berkisar dari <50 – 100 cmol (+) kgbila
dinyatakan atas dasar berat, tetapi relatif rendah bila dinyatakan atas dasar
volume (Radjagukguk 2007 dalamNoor 2001). KTK gambut terutama
ditentukan oleh fraksi lignin dan substansi humat yang relatif stabil,
termasuk asam-asam humat dan fulvat yang bersifat hidrofilik dan agresif
yang biasanya membentuk kompleks stabil dengan ion-ion logam (Noor
2001).
d. Nisbah C/N
Menurut Broadbent (1957) dan Schroeder dalamNotohadiprawiro
(1999), nisbah C/N berguna sebagai penanda kemudahan perombakan
bahan organik dan kegiatan jasad renik tanah. Nisbah C/N berkisar antara
31 – 49. Bila nilai C/N rasio lebih besar dari 30 akan terjadi immobilisasi
N oleh mikrobiologi tanah untuk memenuhi kebutuhan metabolismenya.
Sedangkan, bila rasio C/N antara 20 -30, dapat terjadi immobilisasi
maupun pembebasan N ke dalam tanah gambut. Dengan rasio C/N tanah
gambut di atas 30 maka N pada tanah gambut ini sukar tersedia bagi
tanaman (Barchia 2006).
Meskipun kandungan N-total gambut terkategori tinggi, namun unsur hara
N relatif kurang tersedia bagi tanaman karena N dalam bentuk N-organik
dan pada tingkatan C/N rasio yang tinggi tersebut, terjadi proses
immobilisasi N oleh mikrobiologi tanah (Barchia 2006).
e. Unsur Makro Tanah
1. Nitrogen (N)
Nitrogen merupakan hara yang paling banyak mendapat perhatian,
karena jumlah nitrogen yang terdapat di dalam tanah sedikit sedangkan
yang diangkut tanaman berupa panen setiap musim cukup banyak.
Disamping itu senyawa nitrogen anorganik sangat larut dan mudah hilang
ke atmosfer. Selanjutnya efek nitrogen terhadap pertumbuhan akan jelas
dan cepat. Dengan demikian dari banyak segi jelas bahwa unsur nitrogen
19
ini merupakan unsur yang berdaya besar yang tidak saja harus diawetkan
tetapi harus dikendalikan pemakaiannya (Hakim et al. 1986).
Menurut Hakim et al. (1986), nitrogen masuk ke dalam tanah akibat
dari kegiatan jasad renik, baik yang hidup bebas maupun yang
bersimbiosis dengan tanaman. Dalam hal yang terakhir nitrogen yang
diikat digunakan dalam sintesa asam amino dan protein oleh tanaman
inang. Jika tanaman atau jasad renik pengikut nitrogen bebas mati, bakteri
pembusuk membebaskan asam amino dari protein, bakteri amonifikasi
membebaskan amonium dari grup amono, yang kemudian dilarutkan
dalam larutan tanah. Amonium diserap tanaman, atau diserap setelah
nitrogen tanah adalah akibat loncatan suatu listrik di udara. Nitrogen dapat
masuk melalui air hujan dalam bentuk nitrat, jumlah ini sangat tergantung
kepada tempat dan iklim.
2. Fospor (P)
Menurut Hakim et al. (1986), fosfor merupakan unsur hara makro
dan esensial bagi pertumbuhan tanaman. Fosfordalam tanah tidak semua
dapat segera tersedia, hal ini tergantung pada sifat dan ciri tanah serta
pengelolaan tanah. Fosfor bersumber dari deposit batuandan mineral yang
mengandung fosfor di dalam kerak bumi yang diduga mengandung kurang
lebih 0,21% fosfor. Tanaman akan menyerap fosfor dalam bentuk
orthophospat (H2PO4, HPO4dan PO4). Jumlah masing-masing bentuk
sangat tergantung pada pH tanah. Fosfor tersedia di dalam tanah dapat
diartikan sebagai P tanah yang dapat diekstrasikan oleh air dan asam nitrat.
Penambahan unsur ini diharapkan berasal dari pupuk fosfat, pelapukan
mineral-mineral fosfat dan residu hewan serta tanaman. Sedangkan
kehilangan P dapat terjadi karena terangkut tanaman, tercuci dan tererosi.
3. Kalium (K)
Kalium merupakan unsur hara ketigasetelah nitrogen dan fosfor yang
diserap oleh tanaman dalam bentuk ion K+. Muatan positif dari kalium
akan membantu menetralisir muatan listrik yang disebabkan oleh muatan
negatif nitrat, fosfat atau unsur lainnya. Hakim et al. (1986), menyatakan
bahwa ketersediaan kalium merupakan kalium yang dapat dipertukarkan
20
dan dapat diserap tanaman yang tergantung penambahan dari luar, fiksasi
oleh tanahnya sendiri dan adanya penambahan dari kaliumnya sendiri.
Kalium tanah terbentuk dari pelapukanbatuan dan mineral-mineral
yang mengandung kalium. Melalui proses dekomposisi bahan tanaman dan
jasad renik maka kalium akan larut dan kembali ke tanah. Selanjutnya
sebagian besar kalium tanah yang larut akan tercuci atau tererosidan
kehilangan ini dipercepat lagi oleh serapan tanaman dan jasad renik.
Beberapa tipe tanah mempunyai kandungankalium yang melimpah.
Kalium dalam tanah ditemukan dalam mineral-mineral yang terlapuk dan
melepaskan ion-ion kalium. Ion-ion adsorpsi pada kation tertukar dan
cepat tersedia untuk diserap tanaman. Tanah-tanah organik mengandung
sedikit kalium.
4. Kalsium (Ca)
Sumber utama kalsium tanah adalah kerak bumi yang didalamnya
mengandung 3,6% kalsium. Mineral utama yang banyak mengandung
kalsium tanah adalah kalsit (CaCO3) dan dolomitc CaMg(CO3)2. Kadar
kalsium tanah mineral rata-rata adalah 0,4% pada lapisan tanah atas,
sedangkan pada tanah-tanah organik kadarnya lebih tinggi, yaitu dapat
mencapai 2,8%.Mudah tidaknya kalsium dibebaskan tergantung dari
mineral apa dan tingkat kehancurannya (Soepardi 1983).
5. Magnesium (Mg)
Menurut Hakim et al. (1986), sumber utama magnesium tanah adalah
hancurnya mineral primer yang mengandung magnesium, misalnya biotit,
dolomite, holorit, olivine dan lainnya. Kadar rata-rata 0,3% dari total berat.
Ketersediaan magnesium terjadi karena proses pelapukan dari mineral-
mineral yang mengandung magnesium.
21
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Waktu dan Tempat
Penelitian inidilaksanakan pada bulanNovember 2019-Februari 2020 di
wilayah Kanal Panggulonan Panjang Desa Sepojen Kecamatan Kumpeh,
Kabupaten Muaro Jambi. Serta uji analisis di Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas
Pertanian, Universitas Jambi.
3.2 Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sampel tanah gambut dari
daerah penelitian, peta lokasi penelitian dapat dilihat pada lampiran 2, aquades,
K2Cr2O7, CuSO4, NaSO4, H2SO4, NH4CH3CO2, KCl, dan alkohol. Alat yang
digunakan diantaranya adalah bor gambut berpisau, cangkul, ring sampel, GPS
(global position system), parang, tali rafia, kertas label, kantong plastik, meteran,
pH meter, alat dokumentasi, alat-alat tulis. Sedangkan alat yang digunakan di
laboratorium yaitu oven, cawan, desikator, timbangan analitik, kuvet, PH meter,
spektrofotometer, dan kertas whatman (kertas saring).
3.3 Metode Penelitian
Penelitian dilakukan dengan pengambilan sampel pada titik yang telah
ditetapkan dengan metode grid (titik pengamatan). Titik pengamatan berdasarkan
jalur transek tegal lurus dengan tanggul sungai atau arah kontur dengan jarak titik
pengamatan adalah 200 X 200 cm. pengamatan tanah di lapangan dilakukan
dengan pemboboran yang dilakukan untuk mengetahui ketebalan gambut,
kematangan gambut (0-60 cm) dan pengukuran pH (pH meter). Kemudian
mengambil sampel tanah utuh (tidak tenganggu) dengan ring sampel (0-60 cm)
yang di analisis laboratorium yang diamati yaitu bobot isi (BV) (gr/cm3) dan
kadar air (%) menggunakan metode gravimetrik. Selanjutnya mengambil tanah
secara komposit (terganggu) dengan kedalaman 0-60 cm dan di analisis C-
organik, KTK (kapasitas tukar kation), dan N-total.
22
3.4 Pelaksanaan Penelitian
Pelaksaan penelitian ini dilakukan dalam 4 tahap utama yaitu, (1) tahap
persiapan, (2) survei pendahuluan, (3) pengamatan, (4) tahap analisis. Diagram
alir pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Diagram Alir Pelaksanaan Penelitian
3.4.1 Tahap Persiapan
Persiapan penelitian yang akan dilakukan yaitu meliputi persiapan, (1)
studi pustaka yang berhubungan dengan topik penelitian, (2) mengumpulkan
informasi dan peta lokasi penelitian, (3) pembuatan titik pengamatan untuk peta
kerja dengan jarak 200 x 200 m. Titik pengamatan dibuat berdasarkan jalur
transek tegak lurus dengan tanggul sungai.
23
3.4.2 Survei Pendahuluan
kegiatan survei pendahuluanpada penelitian ini meliputi, (1) pengurusan
izin survei dan kerja lapangan dari pihak fakultas dan pengurus Desa Seponjen
sebagai lokasi penelitian, (2) melakukan survei lapangan ke daerah penelitian
untuk memperoleh informasi secara menyeluruh dan resiko yang akan dihadapi,
(3) melakukan pengecekan lapangan sesuai peta kerja dan (4) menyiapakan
perlengkapan survei untuk kelancaran penelitian di lapangan.
3.4.3 Pengamatan
Pada pengamatan ini merupakan kegiatan pengukuran langsung di
lapangan dan pengambilan tanah komposit (terganggu) dan utuh pada titik
pengamatan yang telah ditentukan. Kegiatan pengamatan ini yang akan dilakukan
yaitu :
1. Memasukkan koordinat titik pengamatan yang telah ditentukan
sebelumnya pada peta kerja ke dalam GPS dengan sistem koordinat
universal transverse mercator (UTM).
2. Melakukan deskripsi tentang kondisi fisik lahan meliputi vegetasi atau
penggunaan lahan.
3. Melakukan pengeboran untuk mendapatkan deskripsi tanah seperti
kematangan gambut, ketebalan gambut.Setelah melakukan pengeboran
satu titik pengamatan dan dilanjutkan pada titik pengamatan berikutnya.
4. Pengambilan sampel tanah diambil pada setiap titik lalu dikompositkan
berdasarkan wilayah dengan ketebalan 0-50 cm, 50-100 cm, 100-150 cm,
150-200 cm.
5. Pengambilan sampel tanah utuh menggunakan ring cincin dilakukan pada
satu lokasi dengan kedalaman 60 cm berdasarkan kedalaman gambut yang
dibagi tiga, untuk pengambilan sampel tergantung kondisi tanah dengan
dua kali ulangan untuk perhitungan bobot isi (BV) dan C-organik.
pengambilan sampel diawali dengan diambil 10 cm dari atas permukaan.
6. Pengambilan sampel tanah komposit (terganggu) padatitik dengan
kedalaman 0-60 cm dengan dua kali pengulangan untuk perhitunganN-
total, dan kapasitas tukar kation (KTK).
24
7. Melakukan pengukuran pH tanah gambut di lapangan langsung
menggunakan pH meter.
3.4.4 Pasca Survei Lapangan
Kegiatan pasca (setelah) survei lapangan meliputi :
Melakukan tubulasi dan identifikasi data dari pengamatan secara
keseluruhan pada setiap titik untuk melakukan deleniasi penggunaan
lahan, ketebalan gambut, kematangan gambut, keasaman tanah.
Data-data hasil pengamatan di lapangan dan analisis tanah di laboratorium
diolah untuk dilakukan penelitian sifat fisik dan kimia tanah.
Data-data hasil pengamatan di Lapangan diolah dengan menggunakan
Software ArcGIS untuk pembuatan peta seperti peta kedalaman gambut
dan peta kematngan gambut.
3.5 Parameter yang Diamati
3.5.1 Ketebalan Gambut
Bila lapisan gambut lebih tipis dari 50 cm, maka tidak disebut dengan tanah
gambut. Untuk tanah gambut di klasifikasikan kedalam 4 kelas yaitu :
Gambut tipis 50-100 cm
Gambut sedang 101-200 cm
Gambut dalam 201-300 cm
Gambut sangat dalam > 300 cm
Pengukuran ketebalan gambut menggunakan bor gambut yang dilakukan
langsung di lapangan pada setiap titik yang sudah ditentukan. Dengan cara
pertama memasukkan mata bor gambut ke dalam tanah gambut kemudian
diangkat apabila belum ada tanah mineral yang terangkat, maka mata bor
dimasukkan kembali dengan penambahan batang bor dan angkat lagi, apabila
tanah mineral belum ada maka mata bor dimasukkan kembali dengan penambahan
batang bor, hal ini dilakukan terus menerus secara bertahap sampai mata bor
menyentuh tanah mineral setelah itu baru dicatat ketebalannya gambutnya.
25
3.5.2 Kematangan Gambut
Tingkat kematangan gambut disebut fibrik apabila bahan organiknya
megandung kadar serat tunggi (>75%) dan disebut hermik apabila
megandungkadar serat sedang (17-75%) serta disebut saprik apabila mengandung
kadar serat rendah (<17%) (soil Taxonomy, 1996).
Pengukuran kematangan gambut dilakukan dengan mengambil sejumlah
massa tanah gambut (misalnya satu genggaman tangan) pada setiap titik,
kemudian dipisahkan materi yang masih berupa serat dari massa tanah gambut
tersebut. Selanjutnya perbandingkan jumlah materi serat tersebut terhadap volume
total.
3.5.3 Bobot Isi (BD)
Bobot isi tanah ataubulk density adalah perbandingan antara berat suatu
masa tanah kering mutlak dengan volume total tanah. Tanah tersebut harus dalam
keadaan tidak terganggu (utuh). Satuan bobot isi tanah dinyatakan dalam g/cm3.
Sampel tanah yang akan diuji harus dalam keadaan alami dan struktur tidak
terganggu. Sampel tanah yang diambil dengan core sample akan memudahkan
dalam perhitungan volume dan bobot isi tanah tersebut. Bila sampel tanah hanya
merupakan bongkahan (clod) yang bentuknya tidak beraturan, maka penetapan
volumenya dilakukan dengan cara menimbang berat bongkah tanah tersebut di
dalam air, yang sebelumnya dilapisi dulu dengan lilin/paraffin untuk menghindari
penyerapan.
Pengukuran bobot isi dilakukan sebanyak 2 kali yaitu dengan cara
pengambilan sampel tanah utuh yang diambil di lapangan. Sampel tanah
dimasukkan ke dalam oven dengan pemanasan 105ºC selama 2 kali 24 jam atau
sampai berat tanah konstan.
Bobot isi dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:
𝑩𝒐𝒃𝒐𝒕 𝑰𝒔𝒊 = 𝑩𝒐𝒃𝒐𝒕 𝒕𝒂𝒏𝒂𝒉 𝒌𝒆𝒓𝒊𝒏𝒈 𝒎𝒖𝒕𝒍𝒂𝒌
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒕𝒂𝒏𝒂𝒉 𝒈/𝒄𝒎3 ................................................... (1)
26
3.5.4 Kadar Air
Kadar air tanah dinyatakan sebagai perbandingan antara massa/berat air
yang ada sebelum pengeringan dan setelah pengeringan sampai mencapai
massa/berat air yang tetap pada suhu 105 ̊ C. pengukuran penetapan kadar air
tanah dilakukan di laboratorium. Prosedur pengujian yakni letakkan 30-50 g tanah
gambut pada cawan timbang. Timbang secara hati-hati sampai ketelitiannya 1 atau
0,1 mg. keringkan cawan timbang beserta isi pada suhu 105̊ C selama 24 jam
dalam oven. Setelah 24 jam dinginkan sampel tanah dalam desikator selama 15
menit kemudian timbang sampel tanah dan di catat sebagai berat tanah kering.
Ulangi pengovenan selama 30 menit dan di dinginkan dalam desikator kembali
selama 15 menit kemudian di timbang. Ulangi prosedur tersebut hingga berat
konstan kurang lebih 0,002 g. pungukuran tersebut menggunakan persamaan
sebagai berikut :
Kadar air tanah (% berat) = berat basah−berat kering
berat kering X 100%................................(2)
Keterangan :
Berat basah = (berat tanah + berat cawan) sebelum dioven – berat cawan
Berat kering = (berat tanah + berat cawan setelah dioven – berat cawan)
3.5.5 Kemasaman Tanah
Ph tanah menunujukkan banyaknya ion hidrogen (di dalam tanah). Makin
tinggi kadar ion didalam tanah, semakin masam tanah tersebut. Bila kandungan H
sama maka tanah bereaksi netral yaitu mempunyai Ph = 7 (Hardjowigeno, 2010).
Pengukuran penetapan Ph tanah dilakukan di lapangan langsung
menggunakan Ph meter.
3.5.6 C-organik
Penetapan C-organik dilakukan dengan beberapa tahap : sampel tanah
dikeringkan dengan oven sehingga didapatkan berat kering mutlak tanah. Sampel
tanah yang kering mutlak dimasukkan kedalam furnace pada suhu 550°C untuk
pembakaran.Pembakaran dan pengabuan dilakukan selama 4-6 jam sampai
seluruh karbon pada gambut hilang hingga yang tersisa adalah bahan mineral yang
27
terkandung di dalam gambut. Kadar C-organik dihitung mengunakan rumus
sebagai berikut:
Bahan organik (%) = 𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ (𝑔𝑟)−𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑏𝑢 (𝑔𝑟)
𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ (𝑔𝑟)× 100 %
C-organik = 𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑘
1,724 …………………………………………………… (3)
Adapun langkah kerja perhitungan C-organik tanah sebagai berikut,
Analisis C-organik, sampel yang digunakan adalah sampel tanah utuh yang sudah
dikeringkan dengan oven dan untuk tanah komposit di kering anginkan terlebih
dahulu, kemudian di oven agar kering mutlak. Pisahkan sampel setiap lapisan
permukaan, kemudian ditimbuk untuk menghancurkan tanah-tanah yang
mengumpal dan kayu-kayu didalamnya dan begitu untuktanah komposit tiap
wilayah kedalaman yang berbeda.Masukkan sampel tanah kedalam cawan
sebanyak 10 g dan kemudian dicatat berat cawan + tanah, setelah semua sampel
dimasukan kedalam cawan, masukkan cawan ke dalam furnace, dan atur posisi
didalamnya agar pada saat pengambilan tidak tertukar. Setelah di furnace selama
6 jam dengan suhu 550°C, matika furnace dan biarkan selama 12 jam sampai suhu
didalamnya normal. Angkat semua sampel keluar lalu ditimbang sehingga didapat
jumlah bahan organik didalam tanah tersebut. Perhitungan C-organik tinggal
mengkonversikan dengan rumus yang sudah ditetapkan.
3.5.7 Analisis N-Total
Langkah kerja analisis N-total adalah 1 g sampel tanah, 0,1 selenium black,
0,1 g cupry sulfate (CuS04) dan 2 g natrium sulfat (Na2SO4) dalam cawan
porselen. Lalu masukkan dalam tabung digester, tambahkan 6 ml asam sulfat
(H2SO4) dan destruksi sampel tanah dalam heating black selama 270 menit
dengan suhu 380 ᶱC setelah selesai proses destruksi tambahkan 10 ml aquades,
larutan hasil destruksi dalam tabung digester dimasukkan dalam kjeltec destilasi
untuk proses destilasi. Larutan hasil destilasi berwarna biru yang tertampung
dalam erlemenyer 250 ml dititrasi menggunakn larutan asam sulfat (H2SO4) 0,02
N. Catat volume larutan asam sulfat (H2SO4) 0,02 N yang digunakan. Perhitungan
N-total dapat di hitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut :
28
N-total = 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑇𝑖𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑋 𝐾𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖 𝐻2𝑆𝑜4 𝑥 0,014
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑥 100%.....................................(4)
Keterangan :
Hasil titrasi : Banyaknya larutan H2SO4 yang digunakan pada saat titrasi
Kosentrasi H2SO4 : 0,0199
Berat sampel : 3
0,014 : Berat atom N/100
3.5.8 KTK (Kapasitas Tukar Kation)
Proses pengujiannya yakni timbang sampel tanah kemudian di masukkan ke
dalam tabung kocok, berikan ammonium acetate, kocok selama 2 jam lalu saring
kedalam tabung kocok menggunkaan kertas whatman nomor 42. Tanah yang
tinggal di kertas di bilas menggunakan alkohol. Tanah yang tertinggal di kertas
saring yang telah di bilas menggunakan alkohol kemudian dikeringkan anginkan
lalu di bersihkan menggunakan KCl, kocok menggunakan mesin shaker selama 1
jam, saring kembali menggunakan kertas whatman nomor 42 ke dalam labu ukur
dan tambahkan KCl sampai batas tanda garis. Larutan dalam labu dimasukkan
dalam tabung digester untuk destilasi menggunakan alat kjeltec destilasi. Terakhir,
larutan hasil destilasi berwarna biru yang tertampung dalam erlemenyer dititrasi
menggunakan larutan asam sulfat (H2SO4) 0,02 N. Adapun untuk menghitung
KTK dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut :
N = Hasil Titrasi – Blanko X 0,8............................................................(5)
Keterangan :
Hasil titrasi : banyaknya larutan H2SO4yang digunakan pada saat titrasi
Blanko : 0,7
3.6 Analisis data
Data karakteristik tanah gambut yang diperoleh dianalisis secara deskriptif
dan dicocokkan secara matching dengan tingkat kematangan, ketebalan gambut,
bobot isi (BD), C-Organik, ph tanah, N-total dan KTK untuk melihat apakah ada
perubahan akibat penggunaan lahan.
29
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Secara umum lokasi penelitian merupakan hamparan lahan gambut yang
telah dimanfaatkan oleh masyarkat sekitarnya untuk lahan pertanian. Komoditas
pertanian yang terdapat pada lokasi pertanian umumnya berupa perkebunan sawit
dan karet baik itu milik perusahaan maupun milik masyarakat sekitar. Secara
administrasi berada di Desa Seponjen Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro
Jambiyang mana berbatasan dengan Desa Air Hitam Laut di sebelah Timur, Desa
Sogo di sebelah Utara, di Desa Rantau Panjang di sebelah Barat dan Desa Bungur
disebelah Selatan. Secara geografis Desa Seponjen terletak pada posisi 1°28’20”-
1°30’20” Lintang Selatan dan diantara 103°59’05’’-104°00’11” Bujur Timur.
Desa seponjen merupakan salah satu desa Kecamatan Kumpeh yang juga
dialiri Sungai Kumpeh. Lokasi penelitian berbatasan dengan PT. Bukit Bintang
Sawit pada sebelah utara, berbatasan dengan PT. Wana Seponjen Indah pada
sebelah selatan, berbatasan dengan kebun sawit rakyat pada sebelah barat, dan
berbatasan dengan Taman Hutan Raya pada sebelah timur. Lokasi penelitian
berjarak ± 62 km dari ibukota Provinsi Jambi dan dapat menggunakan kendaraan
roda dua ataupun roda empat dengan memakan waktu ± 2 jam perjalanan.
5.1.1 Ketebalan Gambut
Berdasarkan kriteria kedalamannya, gambut dapat diklasifikasikan sebagai
gambut tipis (50-100 cm), sedang (100-200 cm), dalam (200-300 cm), dan sangat
dalam ( > 300 cm) ( Dariah dkk., 2011). Hasil dari pengukuran dilapangan
diperoleh pada lahan gambut bervegetasi sawit, pinang, karet, semak belukar
(pakis), dan lahan campuran. Ketebalan tanah gambut pada lokasi penelitian dapat
dilihat pada Tabel 2.
30
Tabel 2. Ketebalan Tanah Gambut Lokasi Penelitian
Wilayah Ketebalan
(cm)
Kode Titik Boring
(TB) Kategori
300-400 TB0.1, TB0.2, Dalam
>400-500 TB0.3, TB1.3, TB1.2,
TB1.1, TB1.0, Sangat Dalam
>500-600 TB0.4, TB1.4, TB2.4,
TB3.4, TB2.0, TB2.1,
TB2.2, TB2.3
Sangat Dalam
>600 TB4.4, TB4.3, TB3.3,
TB3.2 Sangat Dalam
Sumber: Hasil Pemboran November 2019 – Januari 2020
Ketebalan gambut pada Tabel 2 menunjukkan bahwa secara umum
kedalaman gambut di lokasi penelitian termasuk kategori sangat dalam dimana
dengan ketebalan >300 cm. sebaran kedalaman gambut di lokasi penelitian ini
dipengaruhi oleh sungai utama (sungai kumpeh), sehingga jauh jarak dari sungai
maka kedalaman gambutnya akan semakin dalam, hal tersebut dapat dilihat pada
peta kedalaman gambut (Gambar 3). Hasil penelitian Indrayanti et al (2015)
menunjukkan bahwa jarak sungai tidak mempengaruhi sebaran kedalaman
gambut, perbedaan kedalaman gambut diduga disebabkan adanya perbedaan
tutupan lahan sehingga menyebabkan akumulasi bahan 30rganic gambut juga
berbeda. Faktor lain yang menjadi perbedaan kedalaman gambut yaitu keadaan
lapisan mineral dibawah tanah gambut yang tidak beraturan atau bergelombang.
Keda;aman gambut juga dapat menggambarkan proses terjadinya pembentukan
gambut.
Gambut dengan ketebalan >300 cm diperuntukan sebagai kawasan
konservasi sesuai dengan keputusan presiden No. 32/1990. Hal ini disebabkan
oleh semakin tebal gambut, maka semakin penting pula fungsinya dalam
memberikan perlindungan terhadap lingkungan dan sebaliknya kondisi
lingkungan lahan gambut semakin rapuh apabila dikonversi menjadi lahan
pertanian. Pertanian dilahan gambut tebal lebih sulit pengelohannya dan mahal
biayanya karena kesuburannya rendah dan daya dukung tanahnya rendah sehingga
sulit dilalui kendaraan pengangkutan sarana pertanian dan hasil panen (Agus dan
Subsika, 2008). Semakin tebal lapisan gambut maka kesuburan tanahnya semakin
31
semakin menurun sehingga tanaman sulit mencapai lapisan mineral yang berada
dibawahnya. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan tanaman terganggu serta
mengakibatkan tanaman mudah condong dan roboh khususnya pada tanaman
tahunan atau tanaman perkebunan (Suswati et all, 2011) .
Gambar 3. Peta Kedalaman Gambut
5.1.2 Kematangan Gambut
Berdasarkan tingkat kematangan /dekomposisi bahan organik, gambut
dibedakan atas 3 jenis yaitu fibrik (gambut mentah), hemik (gambung setengah
matang), dan saprik (gambut matang) (Gambar 5). Di Lapagan, tingkat
kematangan gambut ditentukan dengan metode perasan yang dapat ditunjukkan
dengan melihat hasil cairan dan sisa bahan perasan dengan tangan. Tingkat
kematangan gambut bervariasi karena terbentuk dari bahan, kondisi lingkungan
dan waktu yang berbeda. Tanah gambutyang matang akan cenderung lebih halus
dan lebih subur sebaliknya yang belum matang, banyak mengandung serat dan
kurang subur (Najiyati,. Dkk 2005).Tingkat kematangan lapisan permukaan
dilapangan ditentukan dengan menggunakan metode peras (Van Pos). Gambar
pengamatan tingkat dekomposisi lapisan permukaan dapat dilihat pada gambar 3.
32
Gambar 4. Pengamatan tingkat dekomposisi lapisan permukaan
Table 3. Tingkat Kematangan Lapisan Permukaan
No Kematangan Lapisan
Permukaan (0-60 cm)
Kode Titik Boring
1 Hemik TB0.1, TB0.2, TB1.1, TB1.2, TP2.0,
TB2.1, TB3.1,
2 Saprik TB0.3, TB0.4, TB1.0, TB1.3, TB1.4,
TB2.2, TB2.3, TB2.4, TB3.2, TB3.3,
TB3.4, TB4.3, TB4.4
Sumber: Hasil pengamatan lapangan November 2019-Januari 2020
Pada Tabel 3 data yaag diperoleh dilapangan bahwa tingkat kematangan
pada lapisan permukaan di lokasi penelitian telah mengalami proses dekomposisi
lanjut, sehingga tingkat kematangan pada lapisan permukaan lebih matang.
Bervariasinya tingkat kematangan lapisan permukaan dipengaruhi oleh tinggi
muka air gambut. Ketinggian muka air gambut akan mempengaruhi tingkat
kematangan lapisan permukaan dan laju dekomposisi tanah gambut pada lapisan
permukaan. Secara umum tingkat dekomposisi pada lapisan gambut pada lapisan
atas dan di atas permukaan air tanah atau tinggi atau lebih lanjut daripada lapisan
gambut di bawah muka air tanah. Berdasarkan penilaian terhadap perubahan
kematangan maka secara ekologis yang menjadi faktor utama yang mempengaruhi
adalah tinggi muka air tanah (water level) (Suwondo et all, 2010).
Berdasarkan Las et all (2008) menyatakan bahwa pengaturan tata air
makro maupun mikro sangat mempengaruhi karakteristik lahan gambut.
Penurunan muka air tanah menyebabkan lapisan gambut di atas muka air yang
mengalami proses dekomposisi yang lebih lanjut daripada lapisan gambut di
bawah muka air tanah. Pada kematangan fibrik, air tanah berada dekat dengan
permukaan tanah bahkan relative lebih sering tergenang sehingga bahan organik
sulit terdekomposisi. Kematangan hemik merupakan zona naik turunya muka iar
33
tanah sehingga sebagian bahan tanah organik sudah lanjut terdekomposisi dan
sebagian belum terdekomposisi lanjut pada kematangan saprik tinggi muka air
tanah berada di bawah permukaan tanah gambut dan dalam kondisi aerobic
sehingga sebagian besar bahan organik telah terdekomposisi sempurna (Nugroho
dan Budi, 2012).
Gambar 5. Keamatangan Gambut
5.1.3 Bobot Isi (BD)
Bobot isi (BD) suatu tanah gambut merupakan parameter yang paling
penting. Bobot isi (BD) tanah gambut sangat rendah berkisar antara 0,1 sampai
0,3 g.cm-3 dan dipengaruhi tingkat kematangan gambut, campuran dengan bahan
mineral, kadar lengas, dan kadar abu. Tanah yang mempunyai kadar abu ynag
tinggi dan makin banyak bercampur terdekomposisi, berat volumenya semakin
besar (Radjagukguk, 1997).
Menurut Kurnain (2010) menyatakan bahwa bobot isi (BD) dapat
digunakan untuk menilai tingkat kematangan gambut < 0,075 g.cm-3 termasuk
tingkat kematangan fibrik, BV > 0,195 g.cm-3 termasuk tingkat kematangan
saprik, sedangkan tingkat kematangan hemik berada diantara keduanya. Nilai
bobot isi (BD) tanah diambil pada masing-masing titik dengan kedalaman sampai
60 cm, dapat dilihat pada Tabel 4.
34
Tabel 4. Bobot Isi (BD) Tanah Gambut dari Lapisan 0-60 cm
No Kode Titik
Boring
Bobot Isi (BD) Tanah (g/cm3)
Kadar Air (%)
Lapisan (cm)
0-20 20-40 40-60
1 TB 0.1 0.14 0.23 0.17 416
2 TB 0.2 0.27 0.28 0.37 324
3 TB 0.3 0.43 0.29 0.45 63
4 TB 0.4 0.50 0.37 0.31 192
5 TB 1.0 0.13 0.18 0.14 517
6 TB 1.1 0.15 0.15 0.15 480
7 TB 1.2 0.20 0.15 0.15 410
8 TB 1.3 0.22 0.14 0.14 410
9 TB 1.4 0.18 0.19 0.16 462
10 TB 2.0 0.13 0.17 0.16 473
11 TB 2.1 0.12 0.12 0.17 283
12 TB 2.2 0.19 0.14 0.15 502
13 TB 2.3 0.18 0.14 0.14 466
14 TB 2.4 0.23 0.20 0.14 510
15 TB 3.1 0.15 0.13 0.17 470
16 TB 3.2 0.13 0.11 0.14 557
17 TB 3.3 0.15 0.12 0.11 643
18 TB 3.4 0.19 0.10 0.14 605
19 TB 4.3 0.12 0.12 0.12 640
20 TB 4.4 0.14 0.13 0.15 530
Sumber : Hasil analisis Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Partanian (UNJA)
Nilai bobot isi (BD) tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat
kematangan gambut dan kedalaman gambut.Tabel 4 menunjukkan dari hasil
penelitian, lapisan atas gambut ternyata memiliki nilai bobot isi(BD) yang relatif
tinggi bila dibanding dengan lapisan bawah gambut.Nilai bobot isi(BD) gambut
dilokasi penelitian mendekati nilai bobot isi(BD) tanah gambut pada umumnya
yaitu berkisar antara 0.01 – 0.2 g/𝑐𝑚3. Proses dekomposisi yang terjadi pada tiap
kedalaman berbeda-beda. Nilai bobot isi yang rendah diakibatkan oleh adanya
rongga pada gambut yang dipengaruhi oleh adanya akar-akar tumbuhan maupun
dari kayu pepohonan. Nilai bobot isi yang tinggi diakibatkan oleh terjadinya
pemadatan dan pengaruh lapisan liat (Batubara, 2009). Selanjutnya Noor (2001),
menyatakan bahwa bobot isi gambut yang rendah mengakibatkan daya dukung
35
tanah rendah sehingga tanaman mengalami kendala dalam menjangkarkan
akarnya akibatnya banyak tanaman tahunan yang tumbuh condong dan tumbang.
Dilihat pada Tabel 4 tanah gambut mempunyai kapasitas mengikat air atau
memegang air yang relatif sangat tinggi atas dasar berat kering. Noor (2001)
menyatakan bahwa kemampuan menyerap air pada tanah gambut tergantung pada
tingkat kematangannya. Nilai kadar air juga tergantung terhadap tinggi rendahnya
kondisi tinggi muka air gambut. Kadar air pada kematangan pada masing- masing
titik bobot berkisar 192 -640 % dari kriteria hemik sampai saprik. Sedangkan
menurut Saribun (2007), ketersediaan air tanah bukan hanya berdasarkan
kematangan saja tetapi di pengaruhi juga oleh curah hujan atau air irigasi.
5.1.4 Kemasaman Tanah (pH)
Kemasaman tanah merupakan salah satu parameter penting dalam analisis
karakteristik suatu tanah gambut. Hal ini disebakan karena adanya korelasi yang
erat antar nilai pH dengan ketersediaan unsur hara di dalam tanah. Peningkatan
nilai pH tanah yang masih tergolong sangat asam diduga karena adanya proses
dekomposisi yang sedang berlanjut pada lahan gambut ( Rini et al, 2009),
menyatakan bahwa proses dekomposisi yang sedang terjadi pada lahan gambut
menghasilkan asam-asam organik yang bersifat asam. Berdasarkan hasil analisis,
dilihat pada tabel 5 rata-rata pH tanah di kawasan lahan penelitian mulai dari agak
masam sampai sangat masam (3-5). Hal ini sejalan dengan pendapat Hartatik et
all.(2004) bahwa lahan gambut umumnya mempunyai tingkat kemasaman yang
relatif tinggi dengan kisaran pH 3-5.
Gambar 6. Pengamatan pH
Tabel 5. Kriteria penilaian kemasaman tanah (pH)
36
No Kode Titik Boring Nilai Rata-rata Ph
1 TGVSP 4.33
2 TGVSI 5.00
3 TGVP 4.00
4 TGVC 4.5
5 TGVK 3.83
6 TGVSB 3.5
7 TGVSP 3.66
Sumber : Hasil pengamatan lapangan November 2019-Januari 2020
Berdasarkan Tabel 5, tanah gambut di lokasi penelitian tergolong sangat
asam dimana nilai pH berkisar 3-5 sama seperti halnya ditemukan pada tanah
gambut di daerah lainnya. Nilai pH yang sangat masam terdapat pada TGVSB
dengan nilai 3,5. Kemudian dilanjutkan TGVSP dengan nilai 3,66 selanjutnya
pada TGVSK mendapatkan nilai sebesar 3,83. Pada TGVP mendapatkan nilai
sebesar 4 dan pada TGVSP mendapatkan nilai sebesar 4,33 selanjutnya pada
TGVC mendapatkan nilai sebesar 4,5. Kemudian nilai pH yang masam terdapat
pada TGVSI dengan nilai sebesar 5. Tingginya kemasaman tanah gambut
disebabkan oleh tingginya kandungan asam-asam organik dan ion hydrogen dari
pelapukan bahan organik dalam kondisi anaerob. Seperti ynag dikemukakan oleh
Noor (2001) bahwa organik yang telah mengalami dekomposisi menghasilkan
asm-asam organik yang mempunyai gugus reaktif, seperti Karboksil (-COOH)
dan fenol (OH) yang mendominasi kompleks pertukaran dan bertindak sebagai
asam lemah sehingga dapat terdisosiasi dan menghasilkan ion H+ dan jumlah yang
besar, sehingga pH gambut sangat rendah. Kemasaman tanah gambut cenderung
makin tinggi jika gambut makin tebal. Hasil survey di daerah penelitian memiliki
ketebalan gambut >300 cm dan sangat dalam, sehingga nilai pHnya menjadi
sangat rendah artinya tingkat kemasaman ekstrim (sangat masam).
5.1.5 C-organik
C- organik merupakan indikator dalam penentuan kualitas bahan organik
yang sangat berkaitan dengan laju dekomposisi (Huda et all., 2012). C-organik
menunjukkan kadar bahan organik yang terkandung di dalam tanah tersebut.
Tanah gambut mempunyai tingkat kadar C-organik yang tinggi sampai sangat
tinggi (Soewandita, 2008).
37
Tabel 6. % C-Organik
No Kode Titik Boring Rata-Rata % C-Organik
1 TB 0.1 39.54
2 TB 0.2 35.10
3 TB 0.3 31.43
4 TB 0.4 22.90
5 TB 1.0 53.37
6 TB 1.1 49.87
7 TB 1.2 38.00
8 TB 1.3 44.79
9 TB 1.4 45.29
10 TB 2.0 46.63
11 TB 2.1 52.38
12 TB 2.2 53.71
13 TB 2.3 53.78
14 TB 2.4 52.51
15 TB 3.1 48.09
16 TB 3.2 54.42
17 TB 3.3 55.51
18 TB 3.4 52.62
19 TB 4.3 55.79
20 TB 4.4 53.28
Sumber : Hasil analisis Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Partanian (UNJA)
Berdasarkan Tabel 6 diketahui bahwa nilai kandungan C-Organik pada
kriteria yang sangat tinggi pada masing- masing titik bobot yaitu dengan nilai
sebesar 52, 38 – 55, 79 % sedangkan criteria penilaian kandungn C-Organik tinggi
terdapat pada masing- masing bobot yaitu nilai sebesar 22, 90- 49, 87%.
Kanduangan C-organik tidak memiliki pola yang jelas apabila dibandingkan
antara gambut dengan tingkat kemangan hemik dan saprik, untuk tingkat
kematangan permukaan didominasi saprik, namun pada kedalaman 100 cm
didominasi tingkat kematangan hemik. Berdasarkan hasil pengamatan Suhardjo
dan Widjaja-Adhi 1976 ( dalam safitri 2010) bahwa kandungan C-Organik
gambut meningkat setiap peningkatan ketebalan gambut. Semakin tebal tanah
gambut maka memiliki volume tanah yang besar sehingga kandungan bahan
organik dan C-Organik semakin meningkat.
38
Konversi hutan gambut sekunder menjadi perkebunan kelapa sawit, karet
dan lain sebagainya mengakibatkan terjadinya degradasi kandungan C-Organik
dan bahan organik tanah masih pada kategori sangat tinggi. Degradasi ini diduga
terjadi karena adanya aktifitas dekomposisi oleh mikroorganisme tanah, erosi dan
subsiden yang terjadi akibat aktifitas pada lahan gambut. Kondisi lahan gambut
yang telah didrainase akan merubah anaerob menjadi aerob. Hal ini sesuai dengan
pernyataan Subandar (2011) yang menerangkan bahwa perubahan kondisi anaerob
menjadi aerob pda lahan gambut akan mendorong aktifitas mikroorganisme
perombak bahan organik tanah.
5.1.6 N-total
Menurut Hartatik et all (2011), dalam tanah gambut ketersediaan N untuk
tanaman relatif rendah karena N tanah gambut tersedia dalam bentuk N-organik.
kandungan nitrogen N-total tanah gambut tropis dibeberapa daerah di Iindonesia
tergolong rendah yang berkisar antara 0,3 dan 2,1% (Dohong, 1999), hal yang
sama, yaitu kandungan N-total rendah juga ditemukan Riwandi (2000), yaitu pada
gambut Jambi 0, 54 - 0,70%. Hasil dari pengamatan dapat dilihat pada Tabel 7.
Tabel 7. Kriteria penilaian N-total dan KTK (Kapasitas Tukar Kation)
No Kode Titik Boring N-TOTAL KTK
% cmol+.kg-1
1 TGVSP 0.54 63.15
2 TGVSI 0.43 65.65
3 TGVP 0.46 72.4
4 TGVCV 0.34 73.38
5 TGVK 0.57 67.17
6 TGPSB 0.43 76.36
7 TGVSP 0.17 62.32 Sumber : Hasil analisis Laboratorium BPTP Provinsi Jambi
Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai N-total di daerah penelitian
termasuk dalam kategori rendah sampai kategori sedang (0,17-0,57%). Nilai N-
total dengan kategori rendah yaitu TGVSP sebesar 0,17%, kemudian masih
kategori rendah yaitu TGVCV sebesar 0,34% dan selanjutnya mendapatkan nilai
yang sama dengan kategori sedang yaitu TGVSI dan TGVSB sebasar 0,43%.
39
Kemudian, nilai N-total masih dengan kategori sedang yaitu pada TGVP sebesar
0,46%, TGVSP sebesar 0,54% dan pada TGVK sebesar 0,57%. Meskipun nilai N
total tinggi namun tidak menjamin ketersediaan nitrogen yang cukup bagi
tanaman, hal ini disebabkan oleh terhambatnya mineralisasi dan humifikasi
(Soepardi, 1983). Kandungan N-total hanya akan tersedia setelah tanah gambut
mengalami proses mineralisasi (Radjaguguk, 1991).
Menurut Nugroho et all (2013), hutan gambut sekunder yang dikonversi
menjadi perkebunan kelapa sawit mengalami perubahan kandungan N-total,
namun masih dalam kategori sedang (0,47-0,24%). Pada kelapa sawit usia 26
tahun di kedalaman 100 cm kandungan N-total tergolong rendah (0,2%). Hasil
analisis menunjukkan bahwa kandungan N-total di kedalaman 50cm mengalami
peningkatan pada kebun usia 6 tahun sebesar 0,01% dan kembali turun di usia 26
tahun sebesar 0,24%. Sedangkan pada kedalaman 100cm N-total mengalami
penurunan seiring dengan bertambahnya usia kelapa sawit.
5.1.7 KTK (Kapasitas Tukar Kation)
Kapasitas tukar kation (KTK) pada tanah gambut sangat tinggi, berkisar
100-300 me100g-1 berdasarkan berat kering mutlak tanah gambut (Hartatik dan
Suriadikarta, 2006). Tingginya nilai KTK tersebut disebabkan oleh muatan
negative tergantung pH yang sebagian besar berasal dari gugus karboksilat dan
fenolat, dengan kontribusi terhadap KTK sebesar 10-30% dan penyumbang
terbesarnya adalah derivate fraksi lignin yang tergantung muatan 64-74%
(Charman, 2002).
Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai KTK di daerah penelitian
tergolong dalam nilai sangat tinggi (62,32-76,36 cmol+kg-1) dengan tutupan lahan
semak belukar, kebun karet, kebun kelapa sawit, kebun pinang, kebun campuran.
Kami menduga nilaim KTK di daerah penelitian jika dihubungkan dengan nilai
pH hasil analisis di laboratorium maka nilai yang tertinggi hanya mencapai 76,36
cmol+kg-1 kurang tepat, jika nilai pH hasil analisis lebih tinggi maka nilai KTK
bisa mencapai 100-300 cmol+kg-1, karena muatan negative (yang menentukan
KTK) pada tanah gambut seluruhnya adalah muatan tegantung pH (pH dependent
charge), dimana KTK akan naik bila pH gambut ditingkatkan. Muatan negative
yang terbentuk adalah hasil disosiasi hidroksil pada gugus karboksilat dan fenol.
40
Oleh karena itu, penetapan KTK menggunakan pengekstrak ammonium acetat pH
7 akan menghasilkan nilai KTK yang tinggi, sedangkan penetapan KTK dengan
pengekstrak ammonium klorida (pada pH aktual) akan menghasilkan nilai yang
lebih rendah. KTK tinggi menunjukkan kapasitas jerapan (soption power) lemah,
sehingga kation-kation K, Ca, Mg, dan Na yang tidak membentuk ikatan
koordinasi akan mudah tercuci.
Perubahan nilai kapasitas tukar kation yang masih dalam kategori sangat
tinggi diduga karna kondisi pH tanah yang masih tegolong sangat masam. Hal ini
sesuai dengan pernyataan Winarso (2005) yang mengatakan bahwa perubahan
nilai pH. Tingginya nilai KTK menyebabkan reaksi asam-basa dalam larutan
tanah untuk mencapai keseimbangan memerlukan lebih banyak rektan
(ameliorant) (Maas, 1997). Gambut ombrogen di Indonesia sebagian besar nilai
tukar kationnya ditentukan oleh fraksi lignin dan senyawa humat (Hartatik et all.,
2011). KTK tanah gambut umumnya tinggi dan semakin meningkat sesuai dengan
meningkatnya kandungan bahan organik. adanya intrusi garam dibeberapa tempat
dapat menaikkan nilai KTK (Wahyunto et all., 2015).
41
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tanah
gambut di Desa Seponjen antara lain :
1. Pada lahan penelitian menunjukkan bahwa kedalaman gambut di
lokasi penelitian termasuk kategori sangat dalam dimana dengan
ketebalan >300 cm. Lahan penelitian mempunyai sifat fisik
diantaranya bobot isi (BD) yang menunjukkan gambut ternyata
memiliki berat volume yang sangat tinngi dimana mendapatkan nilai
sebesar 0,2892 g/m3.
2. Lahan penelitian mempunyai sifat kimia diantaranya pH sangat masam
dengan nilai pH sebesar 5. Nilai C-Organik dalam kategori tinggi
dengan nilai 55, 79% begitu juga dengan N-Total dalam kategori yang
sama.
5.2 SARAN
Pengelolaan lahan gambut di Desa Seponjen sudah berlangsung lama
dengan menurunkan TMA (Tinggi Muka Air) sehingga sifat fisik dan kimia
tanah berubah, maka disarankan untuk melakukan pengaturan TMA (Tinggi
Muka Air) dengan sekat kanal atau pintu air agar kerusakan dapat
diminimalisassi.
42
DAFTAR PUSTAKA
Agus, F., K. Hiriah, Dan A. Mulyani. 2011. Pengukuran Cadangan Karbon. Balai
Penelitian Tanah. Bogor.
Agus,F. dan I.G.M.Subiksa. 2008. Lahan Gambut : Potensi untuk pertanian dan
aspek lingkungan. Balai Penelitian tanah dan World Agroforestry Centre
(ICRAFT) Bogor, Indonesia.
Andriesse, J.P. 1988. Natural and Management Of Tropical Peat Soil. Bulletin
Fao Soil. Vol : 59..
Armudin, T.A., Susandi. Dan Oksana. 2017. Analisis Sifat Fisika Tanah Gambut
Pada Hutan Gambut Di Kecematan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi
Riau. Jurnal Agroteknologi. Vol 5. No 2 : 23-28
Arsyad, S. 2000. Konservasi tanah dan air. Ipb press. Bogor.
Aswandi, M. Syarif, Endriani, M. Zuhdi, R.A. Lestari, Sugino.2017. Strategi
Pengelolaan Sekat Kanal Di Desa Seponjen Kumpeh Kabupaten Muaro
Jambi. Laporan Akhir Hasil Penelitian Pilot Project.Universitas Jambi .
Barchia, M. F. 2006. Gambut Agroekosistem dan Transformasi Karbon. UGM
Press. Yogyakarta.
BB Litbang SDLP. 2008. Laporan Tahunan 2008, Konsorsium Penelitian Dan
Pengembangan Perubahan Iklim Pada Sektor Pertanian. Balai Besar
Penelitian Dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian. Bogor.
Boelter, D. H. 1969. Physical properties of peat as related to degree of
decomposition. Proc. Of the soil sci. soc. Of am. No 33: 606-609
Charman D. 2002. Peatlands and Environmental Change. Jhon Wiley & sons. Ltd.
England.
Dikas, T. M. 2010. Karakteristik fisik gambut di riau pada ekosistem (marine,
payau, dan air tawar). Skripsi. Program studi manajemen sumber daya lahan
departemen ilmu tanah dan sumber daya lahan. Fakultas pertanian. Institut
pertanian bogor. Bogor.
Distribusi Ketebalan dan Sifat-sifat Tanah di Hutan Gambut Kalampangan,
Klaimantan Tengah. Jurnal Wanatropika,5(1).
Dohong S. 1999. Peningkatan Produktivitas Tanah Gambut Yang Disawahkan
Dengan Pemberian Bahan Amelioran Tanah Mineral Berkadar Besi Tinggi.
Institut Pertanian Bogor. Bogor. 171 Halaman.
Driessen, P. M. and M. Soepraptohardjo. 1974. Soil for agriculture expansion in
Indonesia. Bogor soil research institute. Bogor.
Driessen, P.M. 1978. Peat Soils. In: IRRI. Soil and Rice. IRRI. Los Banos.
Philipines. 763-779.
Hakim, N., M. N. Nnyakpa., A. M. Lubis., S. G. Nugroho., M. R. Saul., M. A.
Diha., G. B. Hong., dan H. H. Bailey. 1986. Dasar-dasar ilmu tanah.
Unilam. Lampung
Hardjowigeno, S. 2003. Ilmu Tanah. Penerbit Akedemi Pressindo. Jakarta
43
Hardjowigeno, s., 1993. Klasifikasi Tanah dan Pedogenesis. Akademika
Pressindo. Jakarta.
Huda N, Alistair TLJ, Lim HW dan Nopianti R. 2012. Some Quality
Characteristic Of Malaysian Commercial Fish Sausage. Pak J Nutr 11(8):
700-800. ISSN 1680-5194.
Indradewa, D., D. Suswati., B. Hendro., dan D. Shiddieq. 2011. Identifikasi sifat
fisik lahan gambut rasau jaya iii kabupaten kubu raya untuk pegembangan
jagung. Jurnal teknik perkebunan dan PSDL. Vol 1. No 2: 31-40.
Indrayanti L, S.N Marsoem, T.A Prayitno, H. Supriyo dan B Radjagukguk. 2015.
Ismunadji, m. and G. Soepardi.1984. peat soils problems and crop production. In:
organic matter and rice. IRRI. Los Banos. Philiphines. 489-502.
Kurnain A. 2005. Dampak Kegiatan Pertanian dan Kebakaran atas Watak Gambut
Ombrogen. Disertai Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
Yogyakarta.
Maas A. 1997. Pengelolaan Lahan Gambut Yang Berkelanjutan dan Berwawasan
Lingkungan. Jurnal Alami. 2(1) : 12-16
Mutalib, A.A., Lim, J.S., Wong, M.H Dan Koonvai, L. 1991. Characterization,
Distribution And Utilization Of Peat In Malaysia. Prosiding International
Symposium On Tropical Peatland. Malaysia.
Najiyati S, L Muslihat, dan Nyoman N. Suryadiputra. 2005. Panduan Pengelolaan
Lahan Gambut Untuk Pertanian Berkelanjutan Proyek Climate Change,
Forests and Peatlands In Indonesia. Weatlands Internasional- Indonesia
Programme and Wildlife Habitat Canada. Bogor. Indonesia.
Noor, M. 2001. Pertanian Lahan Gambut. Kanisius. Yogyakarta.
Notohadiprawito. 1999. Tanah dan lingkungan. direktorat jenderal pendidikan
tinggi. departemen pendidikan dan kebudayaan. Jakarta.
Nugroho T dan M Budi. 2012. Pengaruh Penurunan Muka Air Tanah Terhadap
Karakteristik Gambut. Fakultas Pertanian. Insitut Pertanian. Bogor.
Nugroho, T. C., Oksana. Dan Aryanti, E. 2013. Analisis Sifat Kimia Tanah Yang
Di Konversi Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Kampar.
Jurnal Agroteknologi. Vol 4. No 1 : 25-30
Purwowidodo. 2005. Mengenal Tanah. Laboratorium Pengaruh Hutan Jurusan
Manajemen Hutan. Fakultas Kehutanan. IPB. Bogor.
Radjagukguk, B. 2000. Perubahan Sifat Fisik dan Kimia Tanah Gambut Akibat
Reklamasi Lahan Gambut Untuk Pertanian. Jurusan Ilmu Tanah,
Universitas Gadjah mada. Indonesia. Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan
Vol.2. No 1:1-15.
Rais, D. S. 2011. Hidrologi Lahan Gambut Dan Peranannya Dalam Kelestarian
Lahan Gambut Tropis. Prosiding Simposium Nasional Ekohidrologi. Jakarta
Riwandi. 2000. Kajian Stabilitas Gambut Tropika Indonesia Berdasarkan Analisis
Kehilangan Karbon Organik, Sifat Fisikomia dan Komposisi Bahan
Gambut. Disertai Doktor. Program Pascasarjana IPB. Bogor.
44
Sagiman, S. 2007. Pemanfaatan Lahan Gambut Dengan Perspektif Pertanian
Berkelanjutan. Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura. Pontianak.
Saribun. 2007. Pengaruh Jenis Penggunaan Lahan dan Kelas Kemiringan Lereng
Terhadap Bobot Isi, Porositas Total, dan Kadar Air Tanah Pada Sub-DAS
Cikapundung Hulu. Skripsi. Jurusan Ilmu Tanah Fkultas Pertanian.
Universitas Padjajaran.
Sianturi, F. 2006. Perubahan sifat fisik dan kimia tanah pada areal bekas terbakar
di tegakan puspa (schima wallichii korth). Skripsi. Jurusan budidaya hutan.
Fakultas kehutanan. Institute pertanian bogor.
Soepardi. Goeswono. 1983. Sifat Dan Ciri Tanah. Departemen Ilmu Tanah.
Institute Pertanian Bogor. Bogor.
Soewandita H. 2008. Studi Muka Air tanah Gmabut dan Implikasinya Terhadap
Degradasi Lahan Pada Beberapa Kubah Gambut di Kabupaten Siak.
Sulaeman, Suparto dan Eviati. 2005. Analisis kimia tanah, tanaman, air pupuk.
Balai Pelatihan Tanah. Bogor.
Suswati, D., B. Hendro, D. Shiddieq, Dan D. Indradewa.2011. Identifikasi Sifat
Fisik Lahan Gambut Rasau Jaya III Kabupaten Kubu Raya Untuk
Pengembangan Jagung. Jurnal Perkebunan Dan Lahan Tropika. No 1: 31-
40.
Sutanto, R. 2002. Pertanian Organik. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
Suwondo D, S Sabiham, Sumardjo dan B Paramudya. 2010. Analisis Lingkungan
Biofisik Lahan Gambut Pada Perkebunan Kelapa Sawit. Jurnal Hidrolitan,
1(3) :20-28.
Tie, Y. L. And J.S. Lim. 1991. Characteristic And Classification Of Organic Soil
On Malaysia. Proc. Internasioanal Symposium On Tropical Peatland.6-10
May 1991, Kuching, Serawak, Malaysia.
Utama, M.Z.H. Dan W. Haryoko. 2009. Pengujian Empat Varietas Padi Unggul
Pada Sawah Gambut Bukaan Baru Di Kabupaten Padang Pariaman. Jurnal
Akta Agrosia. Vol 12. No 1: 56 – 61.
Wahyunto, D., A. Pitono, D., Dan Sarwani, M. 2013. Prospek Pemanfaatan Lahan
Gambut Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Di Indonesia. Perspektif Vol. 12
No.1: Hal 11-22.
Waraningtyas, I. 2017. Ketebalan Gambut Berdasarkan Jarak Dari Sungai
Indragiri Serta Hubunganya Dengan Sifat Kimia Tanah. Departemen Ilmu
Tanah Dan Sunberdaya Lahan. Fakultas Pertanian.IPB. Bogor.
Widjaja-Adhi, I. P.G. 1988. Physical and chemical characteristic og peat soil of
Indonesia. Indonesia Agricultural Development. No 10 : 59-64
Widyati, E. 2011. Kajian Optimalisasi Pengelolaan Lahan Gambut Dan Isu
Perubahan Iklim. Pusat Litbang Konservasi Dan Rehabilitasi. Tekno Hutan
Tanaman. Vol.4 No.2: 57-68.
45
Yuleli. 2009. Penggunaan beberapa jenis fungsi untuk meningkatkan
pertumbuhan tanaman karet (Hevea brasiliensi) di tanah gambut.Tesis.
sekolah pasca sarana Universitas Sumatera Utara. Medan.
Yulnafatmawati, U., Luki, Dan A. Yana. 2007. Kajian Sifat Fisika Tanah
Beberapa Penggunaan Lahan Di Bukit Gajabuih Kawasan Hutan Hujan
Tropik Gunung Gadut Padang. Jurnal Solum. Vol 4. No 2: 49-61.
46
LAMPIRAN
Lampiran 1. Diagram alir pelaksanaan penelitian
Mulai
Persiapan
Persiapan bahan dan alat, studi pustaka, pegumpulan
informasi dan peta, pembuatan peta titik pengaman
Survei Pendahuluan
Pengurusan izin lokasi, Ground check peta kerja,
menyiapkan perlengkapan pengamatan
Pengamatan
Pengumpulan data
Fisika Kimia
Ketebalan Gambut
Kematangan Gambut
Bobot Isi
Kadar Air Tanah
Kemasaman Tanah (pH)
C-Organik
N-Total
KTK (kapasitas tukar
Kation)
Analisis Data
Selesai
51
Lampiran 6. Kriteria Tingkat Dekomposisi Bahan Organik Menurut Metode
Peras Van Pos
Kode Hasil Peras Bahan organic
H1
Sisa tanaman yang tidak terdekomposisi sempurna, air peras
gambut hanya bewarna sedikit (warna pucat)
H2
Sisa tanaman yang terdekomposisi agak sempurna, air perasan
gambut bewarna coklat muda
H3
Sisa tanaman yang terdekomposisi sangat lemah, air perasan
gambutbewarna coklat dan keruh.
H4
Sisa tanaman yang terdekomposisi lemah, air perasan bewarna
coklat tua dan sangat keruh.
H5
Sisa tanaman yang terdekomposisi agak kuat, tetapi struktur asli
masih dapat terlihat bubur gambut diantara jari ketika diperas.
H6
Sisa tanaman yang terdekomposisi agak kuat, tetapi struktur asli
tanaman tidak jelas, kurang lebih 1/3 bubur gambut keluar dari
sela-sela jari ketika diperas.
H7
Sisa tanaman yang terdekomposisi kuat, kurang lebih ½ bubur
gambut keluar dari sela-sela jari ketika diperas.
H8
Sisa tanaman yang terdekomposisi sangat kuat, kurang lebih 2/3
bubur gambut keluar dari sela-sela jari ketika diperas.
H9
Sisa tanaman yang terdekomposisi hampir sempurna, hampir
seluruh bubur gambut keluar dari sela-sela jari ketika diperas.
H10
Sisa tanaman yang terdekomposisi sempurna, semua bubur gambut
keluar dari sela-sela jari ketika diperas.
Sumber: Muhammad Noor, 2001. Pertanian lahan gambut, Potensi dan Kendala. Kanisius.
Yogyakarta.
Keterangan : H1-H3 : Fibrik (tidak terdekomposisi sempurna/mentah)
H4-H7 : Hemik (Terdekomposisi lemah/setengah matang)
H8-H10 : Saprik (Terdekomposisi sempurna/matang
53
Lampiran 8. Hasil pengamatan kemasaman tanah
No TITIK
BORING
Nilai Ph Nilai Rata-
rata pH Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3
1 TGVSP 5 4 4 4.33
2 TGVSI 5.5 4 5.5 5.00
3 TGVP 3 5 4 4.00
4 TGVCV 5 4.5 4 4.05
5 TGVK 4 4.5 3 3.83
6 TGPSB 3.5 3.5 3.5 3.05
7 TGVSB 4 3 4 3.67 Sumber : lahan penelitian di Desa Seponjen
54
Lampiran 9. Bobot Isi (BD) Dan Kadar Air Tanah
Titik
Boring
Kedalaman
(cm)
Berat
Cawan (g)
Volume Ring
(g/cm3)
Berat
Basah
(g)
Berat
Kering
(g)
kadar air
( %)
BV Tanah
(g/cm3)
Rata-Rata BV
tanah (g/cm3)
Rata-Rata
Kadar Air
Tanah (%)
Titik 0.1 0 - 20 A 5.1 260.85 201.9 34.2 490 0.13 0.14 481
0 - 20 B 2.6 260.85 214.9 37.6 471 0.14
20 - 40 A 2.7 260.85 217.2 61.6 252 0.24 0.24 321
20 - 40 B 2.7 260.85 240.45 62 287 0.24
40 - 60 A 2.6 260.85 239.8 49 389 0.19 0.17 448
40 - 60 B 5.1 260.85 245 40.4 506 O.15
Titik
Boring
Kedalaman
(cm)
Berat
Cawan (g)
Volume
Ring
(g/cm3)
Berat
Basah
(g)
Berat
Kering
(g)
kadar air
( %)
BV Tanah
(g/cm3)
Rata-Rata BV
tanah (g/cm3)
Rata-Rata
Kadar Air
Tanah (%)
Titik 0.2 0 - 20 A 2.6 260.85 241.7 67.2 259 0.26 0.27 252
0 - 20 B 2.7 260.85 254.1 73.8 244 0.29
20 - 40 A 2.6 260.85 265 68.9 285 0.26 0.28 276
20 - 40 B 2.5 260.85 277.6 75.5 268 0.30
40 - 60 A 2.7 260.85 255.5 47.6 437 0.18 0.36 447
40 - 60 B 2.6 260.85 270.9 48.7 456 0.19
55
Titik
Boring
Kedalaman
(cm)
Berat
Cawan
(g)
Volume
Ring
(g/cm3)
Berat
Basah(g)
Berat
Kering (g)
Kadar Air
(%)
BV
Tanah
(g/cm3)
Rata-Rata
BV tanah
(g/cm3)
Rata-Rata
Kadar Air
Tanah (%)
Titik 0.3 0 - 20 A 2.8 260.85 297.7 112.6 164 0.43 0.43 161
0 - 20 B 2.5 260.85 293.2 113.6 159 0.44
20 - 40 A 2.6 260.85 265 69 284 0.26 0.29 269
20 - 40 B 2.5 260.85 288.8 81.9 252 O.31
40 - 60 A 2.7 260.85 255.5 47.6 437 0.18 0.46 3.60
40 - 60 B 2.6 260.85 275.4 71.8 284 0.28
Titik
Boring
Kedalaman
(cm)
Berat
Cawan
(g)
Volume
Ring
(g/cm3)
Berat Basah
(g)
Berat
Kering
(g)
kadar air
( %)
BV
Tanah
(g/cm3)
Rata-Rata BV
tanah (g/cm3)
Rata-Rata
Kadar Air
Tanah (%)
Titik 0.4 0 - 20 A 4.9 260.85 297.3 129 130 0.49 0.50 128
0 - 20 B 5.1 260.85 300 133.3 125 0.51
20 - 40 A 5.1 260.85 297.2 98.3 202 0.38 0.37 192
20 - 40 B 5.3 260.85 273 96.7 182 0.37
40 - 60 A 4.4 260.85 289.5 85.7 238 0.32 0.30 255
40 - 60 B 5.6 260.85 276 74.2 272 0.28
56
Titik
Boring
Kedalaman
(cm)
Berat
Cawan
(g)
Volume
Ring
(g/cm3)
Berat Basah
(g)
Berat
Kering
(g)
kadar air
( %)
BV
Tanah
(g/cm3)
Rata-Rata
BV tanah
(g/cm3)
Rata-Rata
Kadar Air
Tanah (%)
Titik 1.0 0 - 20 A 2.6 260.85 225.8 37.5 502 0.14 0.13 535
0 - 20 B 2.6 260.85 218.5 32.7 567 0.12
20 - 40 A 2.5 260.85 228.4 62.3 267 0.24 0.18 445
20 - 40 B 2.7 260.85 237.3 32.8 623 0.13
40 - 60 A 2.5 260.85 244.5 33.2 636 0.13 0.14 571
40 - 60 B 5.1 260.85 245 40.4 506 O.15
Titik
Boring
Kedalaman
(cm)
Berat
Cawan
(g)
Volume
Ring
(g/cm3)
Berat Basah
(g)
Berat
Kering
(g)
kadar air
( %)
BV
Tanah
(g/cm3)
Rata-Rata
BV tanah
(g/cm3)
Rata-Rata
Kadar Air
Tanah (%)
Titik 1.1 0 - 20 A 2.6 260.85 214.9 39.3 447 O.15 0.15 459
0 - 20 B 2.7 260.85 223.7 39.3 470 O.15
20 - 40 A 2.6 260.85 215.5 39 452 0.14 0.14 443
20 - 40 B 260.85 207.8 38.9 434 0.14
40 - 60 A 4.8 260.85 254.7 38.2 568 0.14 0.15 536
40 - 60 B 5.1 260.85 245 40.4 510 0.15
57
Titik
Boring
Kedalaman
(cm)
Berat
Cawan
(g)
Volume
Ring
(g/cm3)
Berat Basah
(g)
Berat
Kering
(g)
kadar air
( %)
BV
Tanah
(g/cm3)
Rata-Rata
BV tanah
(g/cm3)
Rata-Rata
Kadar Air
Tanah (%)
Titik 1.2 0 - 20 A 5.2 260.85 236.3 46.1 413 0.18 0.20 371
0 - 20 B 5.1 260.85 260.3 60.5 330 0.23
20 - 40 A 4.9 260.85 245.1 48.2 408 0.18 0.16 522
20 - 40 B 5 260.85 247.2 33.6 636 0.13
40 - 60 A 4.8 260.85 257.6 37.1 594 0.14 0.15 595
40 - 60 B 5.2 260.85 289.5 41.6 596 0.16
Titik
Boring
Kedalaman
(cm)
Berat
Cawan
(g)
Volume
Ring
(g/cm3)
Berat Basah
(g)
Berat
Kering
(g)
kadar air
( %)
BV
Tanah
(g/cm3)
Rata-Rata
BV tanah
(g/cm3)
Rata-Rata
Kadar Air
Tanah (%)
Titik 1.3 0 - 20 A 5.4 260.85 272.2 63.6 328 0.24 0.21 379
0 - 20 B 4.9 260.85 253.8 47.9 430 0.18
20 - 40 A 5 260.85 218.5 37 490 0.14 0.14 519
20 - 40 B 5.1 260.85 228.9 35.4 547 0.13
40 - 60 A 5.2 260.85 279.5 36.7 661 0.14 0.14 334
40 - 60 B 5.2 260.85 269.7 35.1 668 0.13
58
Titik
Boring
Kedalaman
(cm)
Berat
Cawan
(g)
Volume
Ring
(g/cm3)
Berat Basah
(g)
Berat
Kering
(g)
Kadar Air
(%)
BV
Tanah
(g/cm3)
Rata-Rata
BV Tanah
(g/cm3)
Rata-Rata
Kadar Air
Tanah (%)
Titik 1.4 0 - 20 A 2.6 260.85 225.9 44.8 404 0.17 0.18 373
0 - 20 B 2.5 260.85 217.1 49 343 0.18
20 - 40 A 5.2 260.85 267.8 50 435 0.19 0.19 445
20 - 40 B 5.5 260.85 274.1 49.3 455 0.18
40 - 60 A 5.3 260.85 275 42.6 545 0.16 0.16 568
40 - 60 B 5 260.85 269.5 39 591 0.15
Titik
Boring
Kedalaman
(cm)
Berat
Cawan
(g)
Volume
Ring
(g/cm3)
Berat Basah
(g)
Berat
Kering
(g)
Kadar Air
(%)
BV
Tanah
(g/cm3)
Rata-Rata
BV Tanah
(g/cm3)
Rata-Rata
Kadar Air
Tanah (%)
Titik 2.0 0 - 20 A 5.1 260.85 201.9 34.2 490 0.13 0.12 497
0 - 20 B 4.9 260.85 188.3 31.1 505 0.12
20 - 40 A 5.3 260.85 249.4 45.8 445 0.17 0.17 471
20 - 40 B 5.3 260.85 260 43.5 497 0.16
40 - 60 A 5.3 260.85 221.1 44.7 394 0.17 0.16 450
40 - 60 B 5.1 260.85 245 40.4 506 0.15
59
Titik
Boring
Kedalaman
(cm)
Berat
Cawan
(g)
Volume
Ring
(g/cm3)
Berat Basah
(g)
Berat
Kering
(g)
Kadar Air
(%)
BV
Tanah
(g/cm3)
Rata-Rata
BV Tanah
(g/cm3)
Rata-Rata
Kadar Air
Tanah (%)
Titik 2.1 0 - 20 A 5.1 260.85 189.9 36.8 416 0.14 0.18 326
0 - 20 B 5.2 260.85 207.4 61.7 236 0.23
20 - 40 A 5.2 260.85 200.4 32.3 520 0.12 0.12 523
20 - 40 B 5.2 260.85 197.9 31.6 526 0.12
40 - 60 A 6 260.85 238.5 31.7 652 0.12 0.17 481
40 - 60 B 5 260.85 245 59.7 310 0.22
Titik
Boring
Kedalaman
(cm)
Berat
Cawan
(g)
Volume
Ring
(g/cm3)
Berat Basah
(g)
Berat
Kering
(g)
Kadar Air
(%)
BV
Tanah
(g/cm3)
Rata-Rata
BV Tanah
(g/cm3)
Rata-Rata
Kadar Air
Tanah (%)
Titik 2.2 0 - 20 A 5.2 260.85 199.2 48.4 311 0.18 0.18 289
0 - 20 B 5.9 260.85 171.7 46.7 268 0.17
20 - 40 A 6.1 260.85 245.2 37.1 560 0.14 0.14 598
20 - 40 B 5.1 260.85 273.7 37.2 635 0.14
40 - 60 A 5.2 260.85 283.2 41.6 580 0.15 0.15 619
40 - 60 B 5 260.85 282.9 37.3 658 0.14
60
Titik
Boring
Kedalaman
(cm)
Berat
Cawan
(g)
Volume
Ring
(g/cm3)
Berat Basah
(g)
Berat
Kering
(g)
Kadar Air
(%)
BV
Tanah
(g/cm3)
Rata-Rata
BV Tanah
(g/cm3)
Rata-Rata
Kadar Air
Tanah (%)
Titik 2.3 0 - 20 A 5.2 260.85 148.9 45.6 226 0.17 0.17 274
0 - 20 B 6.1 260.85 193.3 45.8 322 0.17
20 - 40 A 4.8 260.85 203.5 36.7 454 0.14 0.14 458
20 - 40 B 5.4 260.85 207.2 36.8 463 0.14
40 - 60 A 5.8 260.85 277.9 35.8 676 0.13 0.13 665
40 - 60 B 6 260.85 271.7 36 654 0.13
Titik
Boring
Kedalaman
(cm)
Berat
Cawan
(g)
Volume
Ring
(g/cm3)
Berat Basah
(g)
Berat
Kering
(g)
Kadar Air
(%)
BV
Tanah
(g/cm3)
Rata-Rata
BV Tanah
(g/cm3)
Rata-Rata
Kadar Air
Tanah (%)
Titik 2.4 0 - 20 A 6 260.85 187.5 60 212 0.23 0.23 271
0 - 20 B 5.1 260.85 260.3 60.5 330 0.23
20 - 40 A 5.4 260.85 240.5 34.2 603 0.13 0.12 619
20 - 40 B 4.8 260.85 245.7 33.4 635 0.12
40 - 60 A 6 260.85 269.1 37 627 0.14 0.13 637
40 - 60 B 6 260.85 260.6 34.9 646 0.13
61
Titik
Boring
Kedalaman
(cm)
Berat
Cawan
(g)
Volume
Ring
(g/cm3)
Berat Basah
(g)
Berat
Kering
(g)
Kadar Air
(%)
BV
Tanah
(g/cm3)
Rata-Rata
BV Tanah
(g/cm3)
Rata-Rata
Kadar Air
Tanah (%)
Titik 3.1 0 - 20 A 5.1 260.85 208 40.7 411 0.15 0.15
459 0 - 20 B 5.4 260.85 234.4 38.6 507 0.14
20 - 40 A 5.3 260.85 234 46.7 401 0.14 0.14
446 20 - 40 B 5.2 260.85 210.5 35.6 491 0.13
40 - 60 A 4.9 260.85 273.4 36.9 640 0.14 0.16
505 40 - 60 B 5.3 260.85 225.4 47.9 370 0.18
Titik
Boring
Kedalaman
(cm)
Berat
Cawan
(g)
Volume
Ring
(g/cm3)
Berat Basah
(g)
Berat
Kering
(g)
Kadar Air
(%)
BV
Tanah
(g/cm3)
Rata-Rata BV
Tanah
(g/cm3)
Rata-Rata
Kadar Air
Tanah (%)
Titik 3.2 0 - 20 A 5.3 260.85 215 35.6 503 0.13 0.13 505
0 - 20 B 5.3 260.85 198.6 32.7 507 0.12
20 - 40 A 5.2 260.85 208.7 29.9 598 0.11 0.11 593
20 - 40 B 5.4 260.85 210 30.5 588 0.11
40 - 60 A 5 260.85 245 34.3 614 0.13 0.13 573
40 - 60 B 5.3 260.85 239.5 37.8 533 0.14
62
Titik
Boring
Kedalaman
(cm)
Berat
Cawan
(g)
Volume
Ring
(g/cm3)
Berat Basah
(g)
Berat
Kering
(g)
Kadar Air
(%)
BV
Tanah
(g/cm3)
Rata-Rata BV
Tanah
(g/cm3)
Rata-Rata
Kadar Air
Tanah (%)
Titik 3.3 0 - 20 A 5.1 260.85 186.2 38.2 387 0.14 0.15 382
0 - 20 B 5.9 260.85 194.5 40.7 379 0.15
20 - 40 A 5.1 260.85 242.2 34.3 606 0.13 0.12 645
20 - 40 B 5.4 260.85 227.1 28.9 685 0.11
40 - 60 A 6 260.85 269.8 24.5 102 0.10 0.10 720
40 - 60 B 4.8 260.85 272.6 30.3 799 0.11
Titik
Boring
Kedalaman
(cm)
Berat
Cawan
(g)
Volume
Ring
(g/cm3)
Berat Basah
(g)
Berat
Kering
(g)
Kadar Air
(%)
BV
Tanah
(g/cm3)
Rata-Rata BV
Tanah
(g/cm3)
Rata-Rata
Kadar Air
Tanah (%)
Titik 3.4 0 - 20 A 4.8 260.85 198.8 46.3 329 0.17 0.18 334
0 - 20 B 5.9 260.85 217.6 49.4 340 0.18
20 - 40 A 6 260.85 264.6 28.7 821 0.11 0.11 829
20 - 40 B 6 260.85 256.7 27.4 836 0.10
40 - 60 A 4.8 260.85 278.3 36.7 658 0.14 0.14 652
40 - 60 B 5.2 260.85 276.7 37.1 645 0.14
63
Titik
Boring
Kedalaman
(cm)
Berat
Cawan
(g)
Volume
Ring
(g/cm3)
Berat Basah
(g)
Berat
Kering
(g)
Kadar Air
(%)
BV
Tanah
(g/cm3)
Rata-Rata BV
Tanah
(g/cm3)
Rata-Rata
Kadar Air
Tanah (%)
Titik 4.3 0 - 20 A 2.7 260.85 225 30.4 640 0.11 0.11 655
0 - 20 B 2.6 260.85 243.5 31.6 670 0.12
20 - 40 A 2.6 260.85 228.6 28.7 696 0.11 0.11 641
20 - 40 B 2.5 260.85 231.8 33.8 585 0.12
40 - 60 A 2.6 260.85 225 30.5 637 0.11 0.12 626
40 - 60 B 2.7 260.85 230.9 32.3 614 0.12
Titik
Boring
Kedalaman
(cm)
Berat
Cawan
(g)
Volume
Ring
(g/cm3)
Berat Basah
(g)
Berat
Kering
(g)
Kadar Air
(%)
BV
Tanah
(g/cm3)
Rata-Rata BV
Tanah
(g/cm3)
Rata-Rata
Kadar Air
Tanah (%)
Titik 4.4 0 - 20 A 5.2 260.85 213.7 46.5 359 0.17 0.14 598
0 - 20 B 6 260.85 256.7 27.4 836 0.10
20 - 40 A 5.4 260.85 196.6 35.4 455 0.13 0.13 495
20 - 40 B 5.1 260.85 221.7 34.9 535 0.13
40 - 60 A 5.9 260.85 226.7 36.1 527 0.13 0.15 498
40 - 60 B 60 260.85 257.8 45.3 469 0.17
64
Lampiran 10. C-organik
Kode
Kedalaman
(cm) BC (g) TK (g) BC + Abu (g)
Abu
(g) BO(%)
C-
Organik(%)
Rata-Rata % C-
Organik
Titik 0.1 0 - 20 A 25.67 10 27.54 1.87 81.3 47.15
39.54
0 - 20 B 20.8 10 22.44 1.64 83.6 48.49
20 - 40 A 26.92 10 31.65 4.73 52.7 30.56
20 -40 B 26.21 10 30.18 3.97 60.3 34.97
40 - 60 A 26.89 10 29.92 3.03 69.7 40.42
40 - 60 B 26.1 10 29.96 3.86 61.4 35.61
Kode
Kedalaman
(cm) BC (g) TK (g) BC + Abu (g)
Abu
(g)
BO(%)
C-
Organik(%)
Rata-Rata % C-
Organik
Titik
0.2 0 - 20 A 29.57 10 33.71 4.14 58.6 33.99
35.10
0 - 20 B 27.18 10 31.98 4.8 52 30.16
20 - 40 A 26.18 10 30.77 4.59 54.1 31.38
20 -40 B 23.8 10 27.78 3.98 60.2 34.91
40 - 60 A 26.46 10 29.41 2.95 70.5 40.89
40 - 60 B 26.46 10 29.69 3.23 67.7 39.26
65
Kode
Kedalaman
(cm) BC (g) TK (g) BC + Abu (g)
Abu
(g) BO(%)
C-
Organik(%)
Rata-Rata % C-
Organik
Titik
0.3 0 - 20 A 27.96 10 33.62 5.66 43.4 25.17
31.42
0 - 20 B 23.33 10 28.27 4.94 50.6 29.35
20 - 40 A 27.21 10 31.81 4.6 54 31.32
20 -40 B 25.13 10 29.35 4.22 57.8 33.52
40 - 60 A 25.55 10 29.55 4 60 34.80
40 - 60 B 25.75 10 29.82 4.07 59.3 34.39
Kode
Kedalaman
(cm) BC (g) TK (g) BC + Abu (g)
Abu
(g) BO(%)
C-
Organik(%)
Rata-Rata % C-
Organik
Titik
0.4 0 - 20 A 26.89 10 34.05 7.16 28.4 16.47
22.90
0 - 20 B 23.77 10 31 7.23 27.7 16.06
20 - 40 A 21.19 10 27.07 5.88 41.2 23.89
20 -40 B 29.62 10 35.91 6.29 37.1 21.51
40 - 60 A 21.94 10 27.06 5.12 48.8 28.30
40 - 60 B 26.45 10 31.08 4.63 53.7 31.14
66
Kode
Kedalaman
(cm) BC (g) TK (g) BC + Abu (g)
Abu
(g)
BO(%)
C-
Organik(%)
Rata-Rata % C-
Organik
Titik
1.0 0 - 20 A 21.22 10 21.86 0.64 93.6 54.29
53.37
0 - 20 B 26.08 10 26.5 0.42 95.8 55.56
20 - 40 A 24.8 10 25.53 0.73 92.7 53.77
20 -40 B 26.87 10 27.4 0.53 94.7 54.93
40 - 60 A 26.56 10 28.54 1.98 80.2 46.51
40 - 60 B 21.13 10 21.62 0.49 95.1 55.16
Kode
Kedalaman
(cm) BC (g) TK (g) BC + Abu (g)
Abu
(g) % BO
% C-
Organik Rata-Rata % C-
Organik
Titik
1.1 0 - 20 A 21.86 10 23.22 1.36 86.4 50.11
49.86
0 - 20 B 23.78 10 24.65 0.87 91.3 52.95
20 - 40 A 21.11 10 22.81 1.7 83 48.14
20 -40 B 22.65 10 23.96 1.31 86.9 50.40
40 - 60 A 21.83 10 23.81 1.98 80.2 46.51
40 - 60 B 21.78 10 22.98 1.2 88 51.04
67
Kode
Kedalaman
(cm) BC (g) TK (g) BC + Abu (g)
Abu
(g) BO(%)
C-
Organik(%) Rata-Rata % C-
Organik
Titik
1.2 0 - 20 A 26.86 10 30.48 3.62 63.8 37.71
38.28
0 - 20 B 25.78 10 29.25 3.47 65.3 37.87
20 - 40 A 26.11 10 29.43 3.32 66.8 38.74
20 -40 B 26.45 10 30.23 3.78 62.2 36.07
40 - 60 A 27.23 10 30.69 3.46 65.4 37.93
40 - 60 B 28.48 10 31.52 3.04 69.6 40.37
Kode
Kedalaman
(cm) BC (g) TK (g) BC + Abu (g)
Abu
(g) BO(%)
C-
Organik(%)
Rata-Rata % C-
Organik
Titik
1.3 0 - 20 A 27.52 10 29.66 2.14 78.6 45.59
44.78
0 - 20 B 26.63 10 29.11 2.48 75.2 43.61
20 - 40 A 27.98 10 30.63 2.65 73.5 42.63
20 -40 B 27.84 10 30.12 2.28 77.2 44.77
40 - 60 A 27.58 10 29.87 2.29 77.1 44.72
40 - 60 B 29.11 10 30.94 1.83 81.7 47.38
68
Kode
Kedalaman
(cm) BC (g) TK (g) BC + Abu (g)
Abu
(g) BO(%)
C-
Organik(%) Rata-Rata % C-
Organik
Titik
1.4 0 - 20 A 29.63 10 31.5 1.87 81.3 47.15
45.28
0 - 20 B 21.97 10 24.38 2.41 75.9 44.02
20 - 40 A 26.89 10 29.32 2.43 75.7 43.90
20 -40 B 23.29 10 25.44 2.15 78.5 45.53
40 - 60 A 26.89 10 29.32 2.43 75.7 43.90
40 - 60 B 27.95 10 29.82 1.87 81.3 47.15
Kode
Kedalaman
(cm) BC (g) TK (g) BC + Abu (g)
Abu
(g)
BO(%)
C-
Organik(%)
Rata-Rata % C-
Organik
Titik
2.0 0 - 20 A 22.88 10 25.37 2.49 75.1 43.56
46.62
0 - 20 B 22.88 10 25.48 2.6 74 42.92
20 - 40 A 21.2 10 22.77 1.57 84.3 48.89
20 -40 B 23.76 10 26.14 2.38 76.2 44.19
40 - 60 A 21.11 10 22.56 1.45 85.5 49.59
40 - 60 B 21.81 10 23.09 1.28 87.2 50.58
69
Kode
Kedalaman
(cm) BC (g) TK (g) BC + Abu (g)
Abu
(g) BO(%)
C-
Organik(%)
Rata-Rata % C-
Organik
Titik
2.1 0 - 20 A 26.09 10 27.22 1.13 88.7 51.45
52.37
0 - 20 B 26.08 10 27.26 1.18 88.2 51.16
20 - 40 A 27.93 10 28.79 0.86 91.4 53.01
20 -40 B 26.46 10 27.27 0.81 91.9 53.30
40 - 60 A 21.85 10 22.73 0.88 91.2 52.90
40 - 60 B 25.11 10 26.07 0.96 90.4 52.43
Kode
Kedalaman
(cm) BC (g) TK (g) BC + Abu (g)
Abu
(g) BO(%)
C-
Organik(%)
Rata-Rata % C-
Organik
Titik
2.2 0 - 20 A 29.58 10 30.5 0.92 90.8 52.66
53.71
0 - 20 B 26.9 10 27.6 0.7 93 53.94
20 - 40 A 27.37 10 28.42 1.05 89.5 51.91
20 -40 B 26.97 10 27.93 0.96 90.4 52.43
40 - 60 A 27.95 10 28.55 0.6 94 54.52
40 - 60 B 26.1 10 26.31 0.21 97.9 56.78
70
Kode
Kedalaman
(cm) BC (g) TK (g) BC + Abu (g)
Abu
(g)
BO(%)
C-
Organik(%)
Rata-Rata % C-
Organik
Titik
2.3 0 - 20 A 26.46 10 27.16 0.7 93 53.94
53.77
0 - 20 B 27.2 10 28.12 0.92 90.8 52.66
20 - 40 A 26.91 10 27.79 0.88 91.2 52.90
20 -40 B 26.07 10 26.6 0.53 94.7 54.93
40 - 60 A 25.1 10 25.7 0.6 94 54.52
40 - 60 B 26.9 10 27.64 0.74 92.6 53.71
Kode
Kedalaman
(cm) BC (g) TK (g) BC + Abu (g)
Abu
(g) BO(%)
C-
Organik(%)
Rata-Rata % C-
Organik
Titik
2.4 0 - 20 A 23.3 10 24.72 1.42 85.8 49.76
52.51
0 - 20 B 23.12 10 24.47 1.35 86.5 50.17
20 - 40 A 23.47 10 24 0.53 94.7 54.93
20 -40 B 27.95 10 28.62 0.67 93.3 54.11
40 - 60 A 23.76 10 24.6 0.84 91.6 53.13
40 - 60 B 26.43 10 27.3 0.87 91.3 52.95
71
Kode
Kedalaman
(cm) BC (g) TK (g)
BC+Abu(g)
Abu
(g) BO(%)
C-
Organik(%)
Rata-Rata % C-
Organik
Titik
3.1 0 - 20 A 26.96 10 28.69 1.73 82.7 47.96
48.08
0 - 20 B 25.12 10 26.98 1.86 81.4 47.21
20 - 40 A 23.29 10 25.07 1.78 82.2 47.67
20 -40 B 26.11 10 27.73 1.62 83.8 48.60
40 - 60 A 26.13 10 27.66 1.53 84.7 49.12
40 - 60 B 27.21 10 28.95 1.74 82.6 47.91
Kode
Kedalaman
(cm) BC (g) TK (g) BC + Abu (g)
Abu
(g)
BO(%)
C-
Organik(%)
Rata-Rata % C-
Organik
Titik
3.2 0 - 20 A 25.61 10 26.57 0.96 90.4 52.43
54.41
0 - 20 B 27.19 10 27.89 0.7 93 53.94
20 - 40 A 25.43 10 25.99 0.56 94.4 54.75
20 -40 B 28.58 10 29.14 0.56 94.4 54.75
40 - 60 A 27.75 10 28.4 0.65 93.5 54.23
40 - 60 B 27.9 10 28.18 0.28 97.2 56.38
72
Kode
Kedalaman
(cm) BC (g) TK (g) BC + Abu (g)
Abu
(g)
BO(%)
C-
Organik(%)
Rata-Rata % C-
Organik
Titik
3.3 0 - 20 A 25.11 10 25.57 0.46 95.4 55.33
55.51
0 - 20 B 27.19 10 27.6 1.41 85.9 49.82
20 - 40 A 25.43 10 25.59 0.01 99.9 57.94
20 -40 B 29.58 10 29.9 0.32 96.8 56.14
40 - 60 A 23.3 10 23.4 0.1 99 57.42
40 - 60 B 27.9 10 28.18 0.28 97.2 56.38
Kode
Kedalaman
(cm) BC (g) TK (g) BC + Abu (g)
Abu
(g)
BO(%)
C-
Organik(%)
Rata-Rata % C-
Organik
Titik
3.4 0 - 20 A 27.67 10 28.98 1.31 86.9 50.40
52.61
0 - 20 B 27.26 10 28.75 1.49 85.1 49.36
20 - 40 A 28.65 10 29.76 1.11 88.9 51.56
20 -40 B 28.41 10 29.1 0.69 93.1 54.00
40 - 60 A 27.97 10 28.5 0.53 94.7 54.93
40 - 60 B 27.54 10 27.98 0.44 95.6 55.45
73
Kode
Kedalaman
(cm) BC (g) TK (g) BC + Abu (g)
Abu
(g)
BO(%)
C-
Organik(%)
Rata-Rata % C-
Organik
Titik
4.3 0 - 20 A 25.63 10 26.1 0.47 95.3 55.27
55.78
0 - 20 B 27.52 10 27.9 0.38 96.2 55.80
20 - 40 A 27.97 10 28.29 0.32 96.8 56.14
20 -40 B 26.59 10 26.96 0.37 96.3 55.85
40 - 60 A 27.97 10 28.31 0.34 96.6 56.03
40 - 60 B 25.58 10 26 0.42 95.8 55.56
Kode
Kedalaman
(cm) BC (g) TK (g) BC + Abu (g)
Abu
(g)
BO(%)
C-
Organik(%)
Rata-Rata % C-
Organik
Titik
4.4 0 - 20 A 23.77 10 24.9 1.13 88.7 51.45
53.27
0 - 20 B 24.6 10 25.65 1.05 89.5 51.91
20 - 40 A 23.76 10 24.58 0.82 91.8 53.24
20 -40 B 24.84 10 25.8 0.96 90.4 52.43
40 - 60 A 23.98 10 24.6 0.62 93.8 54.40
40 - 60 B 24.67 10 24.98 0.31 96.9 56.20
74
Lampiran 11. Dokumentasi Penelitian
Gambaran umum lokasi
penelitian
Gambaran umum lokasi
penelitian
Gambaran umum lokasi
penelitian
Titik boring Pengoboran kedalaman tanah Pengambilan sampel tanah
Sampel tanah Penimbangan sampel basah Proses pengovenan tanah































































































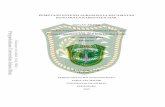


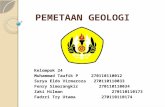





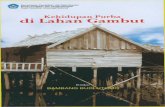
![[2] PEMETAAN SK KD TIK SMA](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6315620c5cba183dbf07f625/2-pemetaan-sk-kd-tik-sma.jpg)



