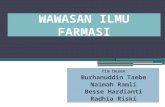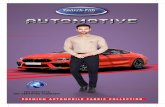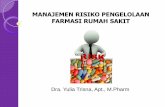Makalah Farmasi DM Syamsudduha G9911006 Copy
Transcript of Makalah Farmasi DM Syamsudduha G9911006 Copy
MAKALAH FARMASI
DIABETES MELITUS:
Oleh :
Syamsudduha
G9911006
Pembimbing:
Dyah Poerwohastuti, S.Farm., Apt
KEPANITERAAN KLINIK ILMU FARMASI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNS / RSUD Dr. MOEWARDI
SURAKARTA
2014
BAB I
PENDAHULUAN
Infeksi pada saluran napas akut merupakan penyakit
yang umum terjadi pada masyarakat, yang juga merupakan
salah satu penyakit penyebab kematian tertinggi pada
balita dan penyebab kematian bayi kedua setelah
gangguan perinatal (WHO, 2008). Salah satu infeksi
saluran napas akut yang paling sering terjadi adalah
rhinitis akut.
Rhinitis akut adalah radang akut mukosa nasi yang
ditandai dengan gejala-gejala rhinorea, obstruksi nasi,
bersin-bersin dan disertai gejala umum malaise dan suhu
tubuh naik (Adams dkk, 2007). Tidak ada terapi spesifik
untuk rhinitis akut selain istirahat dan pemberian
obat-obat simptomatis seperti analgetika, antipiretik
dan dekongestan. Antibiotik hanya diberikan bila
terdapat infeksi sekunder oleh bakteri (Soepardi dkk,
2007).
2
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. INFEKSI SALURAN PERNAPASAN AKUT (ISPA)
1.Definisi
Istilah ISPA atau Infeksi Saluran Pernapasan
Akut diadaptasi dari istilah dalam bahasa Inggris
Acute Respiratory Infections (ARI). Istilah ISPA meliputi
tiga unsur yakni infeksi, saluran pernapasan dan
akut. Infeksi adalah masuk dan berkembangbiaknya
agen infeksi pada jaringan tubuh manusia yang
berakibat terjadinya kerusakan sel atau jaringan
yang patologis. Saluran pernapasan adalah organ
mulai dari hidung hingga alveoli beserta organ
adneksanya seperti sinus-sinus, rongga telinga
tengah dan pleura. Infeksi akut adalah infeksi
yang berlangsung sampai dengan 14 hari. Dengan
demikian ISPA adalah infeksi saluran pernafasan
yang dapat berlangsung sampai 14 hari, dimana
secara klinis tanda dan gejala akut akibat infeksi
terjadi di setiap bagian saluran pernafasan tidak
lebih dari 14 hari (WHO, 2008).
2.Klasifikasi
i. Klasifikasi Berdasar Lokasi Anatomis
Berdasarkan lokasi anatomis (WHO, 2008);
3
1)Infeksi Saluran Pernafasan Akut bagian Atas
(ISPaA)
Infeksi yang menyerang hidung sampai
epiglotis, misalnya rhinitis akut, faringitis
akut, sinusitus akut dan sebagainya.
2)Infeksi Saluran Pernafasan Akut bagian Bawah
(ISPbA).
Dinamakan sesuai dengan organ saluran
pernafasan mulai dari bagian bawah epiglotis
sampai alveoli paru misalnya trakhetis,
bronkhitis akut, pneumoni dan sebagainya.
Infeksi Saluran Pernapasan bawah Akut
(ISPbA) dikelompokkan dalam dua kelompok umur
yaitu (1) pneumonia pada anak umur 2 bulan
hingga 5 tahun dan (2) pneumonia pada bayi
muda yang berumur kurang dari dua bulan.
a) Pneumonia pada anak umur 2 bulan hingga
5 tahun
Klasifikasi pneumonia pada anak umur 2
bulan hingga 5 tahun dengan gejala
klinisnya terdiri dari:
a.1. Pneumonia sangat berat, batuk atau
kesulitan bernapas yang disertai dengan
sinusitis sental, tidak dapat minum,
adanya tarikan dinding dada.
4
a.2. Pneumonia berat, batuk atau kesulitan
bernapas, tarikan dinding dada tanpa
disertai sianosis dan dapat minum.
a.3. Pneumonia, batuk atau kesulitan bernapas
dan pernapasan cepat tanpa penarikan
dinding dada.
a.4. Bukan pneumonia, batuk atau kesulitan
bernapas tanpa pernapasan cepat atau
penarikan dinding dada.
b) Pneumonia pada bayi muda yang berumur
kurang dari 2 bulan
Klasifikasi pneumonia pada bayi muda
yang berumur kurang dari 2 bulan terdiri
dari:
b.1. Pneumonia berat. Pada kelompok umur ini
gambaran klinis pneumonia, sepsis dan
meningitis dapat disertai gejala klinis
pernapasan yang tidak spesifik untuk
masing-masing infeksi,maka gejala klinis
yang tampak dapat saja diduga salah satu
dari tiga infeksi serius tersebut,
yaitu: berhenti menyusu, kejang, rasa
kantuk yang tidak wajar atau sulit
bangun, stidor pada anak yang tenang,
mengi (wheezing), demam (380C) atau suhu
tubuh yang rendah (dibawah 35,50 C),
pernapasan cepat, penarikan dinding
5
dada, sianosis sentral, serangan apnea,
distensi abdomen dan abdomen tegang.
b.2. Bukan pneumonia. Jika bernapas dengan
frekuensi kurang dari 60 kali permenit
dan tidak terdapat tanda pneumonia.
ii. Klasifikasi ISPA pada Batita
1)Pneumonia sangat berat: batuk atau kesulitan
bernafas yang disertai dengan sianosis
sentral, tidak dapat minum, adanya penarikan
dinding dada, anak kejang dan sulit
dibangunkan.
2)Pneumonia berat: batuk atau kesulitan
bernafas dan penarikan dinding dada, tetapi
tidak disertai sianosis sentral dan dapat
minum.
3)Pneumonia: batuk (atau kesulitan bernafas)
dan pernafasan cepat tanpa penarikan dinding
dada. Pernafasan cepat adalah 40 kali per
menit atau lebih pada usia 12 bulan hingga 5
tahun.
4)Bukan pneumonia (batuk pilek biasa): batuk
(atau kesulitan bernafas) tanpa pernafasan
cepat atau penarikan dinding dada.
3.Etiologi
Etiologi ISPA terdiri lebih dari 300 jenis
bakteri, virus dan riketsia. Bakteri penyebab ISPA
6
misalnya dari genus Streptococcus, Haemophylus,
Stafilococcus, Pneumococcus, Bordetella, dan Corynebakterium.
Virus penyebab ISPA antara lain grup Mixovirus
(virus influenza, parainfluenza, respiratory syncytial virus),
Enterovirus (Coxsackie virus, echovirus), Adenovirus, Rhinovirus,
Herpesvirus, Sitomegalovirus, virus Epstein-Barr. Jamur
penyebab ISPA antara lain Aspergillus sp, Candidia
albicans, Blastomyces dermatitidis, Histoplasma capsulatum,
Coccidioides immitis, Cryptococcus neoformans.
Selain itu juga ISPA dapat disebabkan oleh
karena inspirasi asap kendaraan bermotor, Bahan
Bakar Minyak/BBM biasanya minyak tanah dan, cairan
amonium pada saat lahir.
4.Gejala
Penyakit ISPA meliputi hidung, telinga,
tenggorokan (faring), trakhea, bronkus dan paru.
Tanda dan gejala penyakit ISPA pada anak dapat
menimbulkan bermacam-macam tanda dan gejala
seperti batuk, kesulitan bernapas, sakit
tenggorokan, pilek, demam dan sakit telinga.
Sebagian besar dari gejala saluran pernapasan
hanya bersifat ringan seperti batuk dan pilek
tidak memerlukan pengobatan dengan antibiotik.
Namun sebagian anak akan menderita radang paru
(pneumonia) bila infeksi paru ini tidak diobati
dengan anti biotik akan menyebabkan kematian.
7
i. Gejala dari ISPA Ringan
Seseorang dinyatakan menderita ISPA ringan
jika ditemukan satu atau lebih gejala-gejala
sebagai berikut:
1) Batuk
2) Serak, yaitu anak bersuara parau pada waktu
mengeluarkan suara (misalnya pada waktu
berbicara atau menangis)
3) Pilek, yaitu mengeluarkan lendir atau ingus
dari hidung
4) Panas atau demam, suhu badan lebih dari 370
C
ii. Gejala dari ISPA Sedang
Seseorang dinyatakan menderita ISPA sedang
jika dijumpai gejala dari ISPA ringan disertai
satu atau lebih gejala-gejala sebagai berikut:
1) Pernafasan cepat (fast breathing) sesuai umur
yaitu : untuk kelompok umur kurang dari 2
bulan frekuensi nafas 60 kali per menit
atau lebih dan kelompok umur 2 bulan - < 5
tahun : frekuensi nafas 50 kali atau lebih
untuk umur 2 - < 12 bulan dan 40 kali per
menit atau lebih pada umur 12 bulan - <5
tahun
2) Suhu lebih dari 390 C (diukur dengan
termometer)
3) Tenggorokan berwarna merah
8
4) Timbul bercak-bercak merah pada kulit
menyerupai bercak campak
5) Telinga sakit atau mengeluarkan nanah dari
lubang telinga
6) Pernafasan berbunyi seperti mengorok
(mendengkur)
iii. Gejala dari ISPA Berat
Seseorang dinyatakan menderita ISPA berat
jika dijumpai gejala-gejala ISPA ringan atau
ISPA sedang disertai satu atau lebih gejala-
gejala sebagai berikut:
1) Bibir atau kulit membiru
2) Anak tidak sadar atau kesadaran menurun
3) Pernafasan berbunyi seperti orang mengorok
dan anak tampak gelisah
4) Sela iga tertarik ke dalam pada waktu
bernafas
5) Nadi cepat lebih dari 160 kali per menit
atau tidak teraba
6) Tenggorokan berwarna merah
5.Cara Penularan
Penularan penyakit ISPA dapat terjadi melalui
udara yang telah tercemar, bibit penyakit masuk
kedalam tubuh melalui pernafasan, oleh karena itu
maka penyakit ISPA ini termasuk golongan Air Borne
Disease.
9
Penularan melalui udara dimaksudkan adalah
cara penularan yang terjadi tanpa kontak dengan
penderita maupun dengan benda terkontaminasi.
Sebagian besar penularan melalui udara dapat pula
menular melalui kontak langsung, namun tidak
jarang penyakit yang sebagian besar penularannya
adalah karena menghisap udara yang mengandung
unsur penyebab atau mikroorganisme penyebab.
Adanya bibit penyakit di udara umumnya
berbentuk aerosol yakni suatu suspensi yang
melayang di udara, dapat seluruhnya berupa bibit
penyakit atau hanya sebagian daripadanya. Adapun
bentuk aerosol dari penyebab penyakit tersebut ada
dua, yakni droplet nuclei dan dust.
Droplet nuclei adalah partikel yang sangat kecil
sebagai sisa droplet yang mengering.
Pembentukannya dapat melalui berbagai cara, antara
lain dengan melalui evaporasi droplet yang
dibatukkan atau yang dibersinkan ke udara. Droplet
nuclei juga dapat terbentuk dari aerolisasi
materi-materi penyebab infeksi di dalam
laboratorium. Karena ukurannya yang sangat kecil,
bentuk ini dapat tetap berada di udara untuk waktu
yang cukup lama dan dapat diisap pada waktu
bernafas dan masuk ke alat pernafasan.
Dust adalah bentuk partikel dengan berbagai
ukuran sebagai hasil dari resuspensi partikel yang
10
menempel di lantai, di tempat tidur serta yang
tertiup angin bersama debu lantai/tanah.
B. RHINITIS AKUT
1.Definisi
Rhinitis akut adalah radang akut mukosa nasi
yang ditandai dengan gejala-gejala rhinorea,
obstruksi nasi, bersin-bersin dan disertai gejala
umum malaise dan suhu tubuh naik (Adams et al,
2007).
2.Etiologi
Rhinitis disebabkan oleh infeksi virus
(Rhinovirus, Myxovirus, virus Coxsakie dan virus
ECHO) atau infeksi bakteri terutama Haemophylus
Influensa, Steptococcus, Pneumococcus, dan sebagainya
(Adams, 2007; Sobol, 2007; Soepardi, 2007).
Di samping virulensi, faktor predisposisi
memegang peranan penting yaitu faktor eksternal
atau lingkungan yang terpenting adalah faktor
dingin atau perubahan temperatur dari panas ke
dingin yang mendadak, dan faktor internal meliputi
daya tahan tubuh yang menurun dan daya tahan lokal
cavum nasi (Moore, 2003).
11
3.Patofisiologi
Pada rhinitis terjadi perubahan pada mukosa
nasi meliputi stadium permulaan yang diikuti
stadium resolusi. Pada stadium permulaan terjadi
vasokonstrinsik yang akan diikuti vasodilatasi,
udem dan meningkatnya aktifitas kelenjar
seromucious dan goblet sel, kemudian terjadi
infiltrasi leukosit dan desguamasi epitel. Secret
mula-mula encer, jernih kemudian berubah menjadi
kental dan lekat (mukoid) berwarna kuning
mengandung nanah dan bakteri (makopurulent).
Toksin yang berbentuk terbentuk terserap dalam
darah dan lymphe, menimbulkan gejala-gejala umum.
Pada stadium resolusi terjadi proliferasi sel
epithel yang telah rusak dan mukosa menjadi normal
kembali (Adams, 2007; Dhingran, 2007; Rolla,
2009).
4.Stadium dan Gejala
Stadium rhinitis akut adalah sebagai berikut :
a. Stadium prodormal / iskemik
Berlangsung beberapa jam sesudah masa inkubasi
1-3 hari, dengan gejala panas, kering,
gatal pada hidung serta bersin – bersin
b. Stadium hiperemi / katharal
Ditandai dengan hidung tersumbat, ingus encer,
demam dan nyeri kepala.
c. Stadium infeksi sekunder
12
Dalam stadium ini, sumbatan hidung semakin
memberat, sekret menjadi kuning dan lebih
kental.
d. Stadium resolusi/convalescence
Akan terjadi kesembuhan setelah 5 – 10 hari
(Adams, 2007).
Gejala awal rhinitis akut pada stadium
prodromal memang mirip dengan rhinitis alergika
tetapi yang memebedakannya antara lain adanya
gejala umum pada rhinitis akut dan sekret yang
kemudian berubah menjadi kental pada rhinits akut
(Dhigran, 2007; Soepardi, 2007).
5.Tatalaksana
Tidak ada terapi spesifik untuk rhinitis akut
selain istirahat dan pemberian obat-obat
simptomatis seperti analgetika, antipiretik dan
dekongestan. Antibiotik hanya diberikan bila
terdapat infeksi sekunder oleh bakteri (Soepardi
dkk, 2007)
6.Prognosis
Ad vitam : bonam
Ad functional : bonam
Ad sanam : bonam.
13
BAB III
ILUSTRASI KASUS
A. ANAMNESIS
1.Identitas Pasien
a. Nama : Nn. AR
b. Umur : 20 tahun
c. Jenis Kelamin : Perempuan
d. Agama : Islam
e. Alamat : Manahan, Surakarta
f. Pekerjaan : Mahasiswa
g. Suku/ras : Jawa
h. No. RM : 012538xx
i. Tanggal Pemeriksaan : 15 Juli 2014
2.Keluhan Utama
Pasien datang dengan keluhan hidung buntu.
3.Riwayat Penyakit Sekarang
Pasien datang dengan keluhan hidung buntu di
kedua sisi sejak 2 hari sebelum diperiksa. Keluhan
hidung buntu makin lama makin memberat dan membuat
pasien kesulitan bernafas melalui hidung ketika
posisi badan sedang terlentang/saat akan tidur.
Untuk bernafas melalui hidung pasien harus merubah
posisi menjadi duduk tegak terlebih dahulu. Pasien
belum pernah memeriksakan maupun memberikan
14
penanganan ataupun pengobatan terhadap keluhan
hidung buntu.
Keluhan hidung buntu pada pasien disertai
dengan keluar cairan / ingus berwarna putih
bening, tidak berbau dan konsistensinya cair.
Ingus keluar terus menerus dari kedua lubang
hidung dan makin lama makin banyak. Pasien juga
mengeluhkan sering bersin-bersin sejak 4 hari
sebelum diperiksa. Selain itu pasien juga merasa
penciumannya terganggu. Nyeri pada daerah sekitar
hidung, pipi, nyeri di belakang mata dan dahi
tidak dirasakan. Pasien mengalami demam dan sakit
kepala sejak 4 hari sebelum diperiksa. Demam
dirasakan terus menerus, sedangkan sakit kepala
dirasakan hilang timbul. Batuk (-), nyeri
tenggorok (-), nyeri ketika menelan (-), keluhan
di telinga (-), terasa ada cairan di tenggorok
(-).
4.Riwayat Penyakit Dahulu
Riwayat alergi : disangkal
Riwayat asma : disangkal
Riwayat penyakit lain (hipertensi, DM) :
disangkal
Riwayat trauma di bagian kepala :
disangkal
Riwayat operasi di bagian THT-KL :
disangkal
15
5.Lingkungan
Saat ini di keluarga dan lingkungan tidak ada
yang menderita gejala yang sama. Namun beberapa
teman di kampus pasien juga mengalami gejala yang
sama.
6.Gaya Hidup
Diet : rutin, 3 kali sehari
Olah raga : jarang, 1-3 kali per bulan
Istirahat : tidur < 6 jam sehari
Merokok : disangkal
Konsumsi alkohol : disangkal
Konsumsi NAPZA : disangkal
B. PEMERIKSAAN FISIK UMUM
Kesadaran : GSC E4 V5 M6, composmentis
Keadaan umum : Tampak sakit ringan
Tanda vital
Tekanan darah : 110 / 70 mmHg
Frekuensi nadi : 72 kali/menit
Frekuensi napas : 16 kali/menit
Suhu : 37,6 oC
Thoraks : Pengembangan dinding dada
simetris kanan-kiri,
retraksi dinding dada (-)
Jantung : Bunyi jantung I dan II reguler,
bising (-)
16
Paru : Suara dasar vesikuler (+/+),
sonor/sonor, suara
tambahan (-)
Abdomen : nyeri tekan (-), hepar dan lien
tidak teraba, bising
usus dalam batas normal.
C. PEMERIKSAAN THT – KL
1. Telinga
Dextra Sinistra
Daun telinga
Canalis
auricularis
Membrane
timpani
Tragus pain
Hearing loss
Discharge
Normotia
Lapang
Intak
-
-
-
Normotia
Lapang
Intak
-
-
-
Tes
Pendengaran:
Pemeriksaan
Rinne
Pemeriksaan
Weber
Pemeriksaan
Swabach
+ / +
Tidak ada lateralisasi
Kanan dan kiri sama dengan
pemeriksa
17
2. Hidung
Dextra Sinistra
Cavum nasi
Discharge
Concha
inferior
Meatus nasi
medius
Meatus nasi
inferior
Septum nasi
Provokasi lesi
Nyeri pada
daerah
Sinus
frontalis
Sinus
maksilaris
Sinus
sfenoidalis
Sinus
ethmoidalis
Os nasal
Sempit
+, serous
Hipertrofi
Sde
Sde
Deviasi (-)
-
-
-
-
-
Krepitasi (-)
Sempit
+, serous
Hipertrofi
Sde
Sde
Deviasi (-)
-
-
-
-
-
Krepitasi (-)
3. Mulut
18
a. Bibir : kelembaban cukup, sianosis (-), nodul
(-)
b. Ginggiva : udem (-), anemis (-), perdarahan
(-)
c. Gigi : gigi karies (-), gigi tanggal (-)
d. Lidah : papil lidah atrofi (-), geographic tongue
(-)
e. KGB : pembesaran (-), nyeri tekan (-).
4. Tenggorok
Dextra Sinistra
Tonsil
Faring
Adenoid
Lain-lain
T1, hiperemis
(-)
DPP tenang
Hipertrofi (-)
Uvula di tengah
T1, hiperemis
(-)
DPP tenang
Hipertrofi (-)
Uvula di tengah
D. DIAGNOSIS BANDING
Rhinitis akut
Rhinitis vasomotorik
Rhinitis alergi
E. DIAGNOSIS
Rhinitis akut
F. RENCANA PENANGANAN
19
Skin prick test setelah 5 hari bebas obat untuk
mengetahui alergi.
G. TATA LAKSANA
Non Medikamentosa
Edukasi pasien untuk merubah gaya hidup menjadi
lebih sehat dan perbanyak istirahat.
Edukasi pasien bahwa penyakit yang diderita
merupakan self limiting dissease dan obat yang diberikan
hanya mengurangi gejala, bukan menghilangkan
penyebab. Bila keluhan tidak membaik dalam 5
hari, kontrol ke dokter untuk evaluasi obat dan
gejala penyakit dan rencana penanganan.
Medikamentosa
Resep medikamentosa
Puskesmas Manahan
Manahan, Surakarta15 Juli 2014
Dokter : dr. Isna Noor R
R/ Parasetamol mg 500
Nalgestan tab I
M.f.l.a pulv da in cap dtd No. XV
prn (1-3) dd cap I p.c∫
20
Pro : Nn. AR (20 tahun)
Alamat: Manahan, Surakarta
H. PROGNOSIS
Ad vitam : bonam
Ad fungtionam : bonam
Ad sanam : bonam.
21
BAB IV
PEMBAHASAN
A. NALGESTAN
1.FENILPROPANOLAMIN
1. Pengertian
Fenilpropanolamin adalah obat golongan
adrenergic agonis yang digunakan sebagai
dekongestan karena memiliki efek vasokonstritor
yang dihasilkan dari efek alfa adrenergic. Efek
yang ditimbulkan mirip perangsangan saraf
adrenergik. Sebagai obat adrenergic yang
bekerja langsung pada reseptor adrenergic di
membrane sel efektor
2. Farmakodinamik
Fenilpropanolamin adalah simpatomimetik
kerja tak langsung yang memiliki mekanisme aksi
yang sama dengan efedrin tapi kurang aktif
sebagai stimulant di CNS. Fenilpropanolamin
efektif bila diberikan secara oral masa kerja
panjang, tetapi efek pada perangsangan di SSP
kurang. Fenilpropanolamin berkeja pada reseptor
α, β1,dan β2. Efek perifer melalui kerja
langsung dan melalui pelepasan NE endogen. Efek
kardiovaskular sama pada efek epinefrin.
Tekanan sistolik meningkat dan biasanya tekanan
diastolik juga meningkat.
22
3. Farmakokinetik
Pada pemberian oral obat ini cepat
diabsorbsi dari traktus
gastrointestinal,konsentrasi plasma dicapai
sekitar 1 sampai 2 jam setelah dosis oral.
Fenilpropanolamin di metabolisme di hati dalam
bentuk metabolit aktif hidroxilat dan 80% - 90%
diekskresikan tidak dalam bentuk lain ( tidak
berubah) di urin dalam waktu 24 jam.
4. Indikasi
Fenilpropanolamin diberikan untuk
meringankan gejala hidung tersumbat yang
disebakan oleh alergi atau flu.
5. Kontra Indikasi
Dikontraindikasikan untuk pasien yang
mengunakan bersamaan dengan penghambat MAO,
aterosklerosis, hipertensi, hipersensitif pada
simpatomimetika.
6. Efek Samping
Kegelisahan, kelelahan, insomnia,
kepeningan, mual,
hipertensi, tachycardia, arrhythmias.
7. Posologi
Dosis dewasa adalah 25 mg setiap 6 jam,
dosis maksimal adalah 100 mg per hari. Dosis
23
untuk anak 2- 6 tahun 6,25 per 4 jam, jangan
lebih dari 37,5 mg dalam 24 jam. Dosis anak
usia 6-12 tahun adalah 12,5 mg per 4 jam ,
tidak melebihi 75 mg per 24 jam
2.CHLORPHENIRAMINE MALEAT
1. Pengertian
CTM (Chlorpheniramin Maleat) merupakan
golongan antagonis reseptor-H1 (H1-blokers atau
antihistaminika) generasi pertama yang bekerja
mengantagonis histamin dengan jalan memblok
reseptor H1 di otot licin dari dinding
pembuluh, bonchi, saluran cerna, kandung kemih,
dan rahim. Antihistamin H1 merupakan obat yang
dapat menanggulangi gejala hipersensitivitas
secara efektif, terutama bersin dan gatal-gatal
di mata (Tjay dan Rahardja, 2007).
2. Farmakodinamik
Chlorpheniramine mengikat reseptor H1 dengan
cara antagonis kompetitif reversible pada sel
efektor di saluran gastrointestinal, pembuluh
darah dan saluran pernapasan (Katzung, 2001).
3. Farmakokinetik
Chlorpeniramine maleat diabsorpsi baik
melalui pemakaian oral, walaupun obat ini
mengalami metabolisme substansial pada mukosa
gastrointestinal sebelum diabsorpsi dan
24
mengalami reaksi first pass metabolisme di
hati. Data menunjukkan sebesar 25 – 45% dan 35
– 60% dosis tunggal peroral Chlorpeniramine
maleat tablet dan sediaan cair berturut – turut
melewati sirkulasi sistemik sebagai obat tak
berubah (parent drug). Bioavaibilitas sediaan
lepas lambat dari obat ini dikurangi dengan
membandingkan bioavaibilitas pada sediaan
tablet dan cair Chlorpeniramine maleat (Mc
Evoy, 2002). Chlorpeniramine maleat diabsorpsi
relatif lambat dari saluaran pencernaan,
konsentrasi puncak plasma diketahui sekitar 2,5
sampai 6 jam setelah dosis per oral (Sweetman,
2002).
Pada orang dewasa dengan fungsi ginjal dan
hati yang normal, waktu paruh eliminasi
chlorpeniramine maleat yaitu 12 – 43 jam, pada
anak – anak dengan fungsi hati dan ginjal yang
normal, waktu paruh eliminasinya antara 9,6 –
13,1 jam. Pada pasien dengan kerusakan ginjal
kronis dengan hemodialisis, waktu paruh
chlorpeniramine maleat antara 280 – 330 jam
(McEvoy, 2002).
Chlorpeniramine maleat terdistribusi pada
saliva dan sejumlah kecil obat maupun
metabolitnya terdistribusi ke empedu. Secara
invitro, chlorpeniramine maleat kira – kira
25
terikat pada protein plasma sebesar 69 – 72%
(McEvoy, 2002).
Chlorpeniramine dan metabolit –
metabolitnya diekskresi secara lengkap melalui
urin. Ekskresi melalui urin dari
chlorpeniramine dan metabolit – metabolitnya
yang merupakan hasil dari N-dealkilasi
bervariasi terhadap pH urin dan aliran urin.
Penelitian menunjukkan pada orang sehat dengan
fungsi ginjal dan hati yang normal menunjukkan
20% dari dosis tunggal peroral diekskresikan
melalui urin dalam bentuk tak berubah, 20%
sebagai monodesmetilchlorpeniramine, dan 5%
sebagai didesmetilchlorpeniramin (McEvoy,
2002).
4. Indikasi
Pengobatan pada gejala-gejala alergis,
seperti: bersin, rinorrhea, urticaria,
pruritis, dll.
5. Kontra Indikasi
a. Pada pasien dengan hipersensitif terhadap
antihistamin.
b. Pada pasien dengan glaukoma sudut sempit.
c. Pada pasien dengan riwayat asma .
d. Pada pasien dengan terapi obat golongan
MAOIs.
26
e. Pada neonatal dan ibu menyusui (McEvoy,
2002)
6. Efek Samping
Pada sistem pencernaan dapat menyebabkan
mual, muntah, diare, anoreksia. Pada sistem
pernapasan, obat ini dapat menekan sistem
pernapasan dan mengentalkan sekresi bronkial..
Pada saluran kencing, menimbulkan penurunan
sekresi urin. Pada ginjal dapat menyebabkan
poliuria dan pada sistem sirkulasi sitemik
dapat mengakibatkan bradikardia (Katzung,
2001). Menyebabkan sedatif ringan yang
disebabkan oleh depresi SSP dan daya anti
kolinergis (Tjay dan Rahardja, 2007).
B. PARASETAMOL
1.Pengertian
Parasetamol (asetaminofen) merupakan obat
analgetik non narkotik dengan cara kerja
menghambat sintesis prostaglandin terutama di
Sistem Syaraf Pusat (SSP) . Parasetamol digunakan
secara luas di berbagai negara baik dalam bentuk
sediaan tunggal sebagai analgetik-antipiretik
maupun kombinasi dengan obat lain dalam sediaan
obat flu, melalui resep dokter atau yang dijual
bebas. (Darsono, 2002)
2.Farmakodinamik
27
Efek analgesik Parasetamol serupa dengan
Salisilat yaitu menghilangkan atau mengurangi
nyeri ringan sampai sedang. (Gunawan, 2007).
Secara sentral diduga Parasetamol bekerja pada
hipotalamus sedangkan secara perifer, menghambat
pembentukan prostaglandin di tempat inflamasi,
mencegah sensitisasi reseptor rasa sakit terhadap
rangsang mekanik atau kimiawi. Efek antipiretik
dapat menurunkan suhu demam. Pada keadaan demam,
diduga termostat di hipotalamus terganggu sehingga
suhu badan lebih tinggi.
Parasetamol bekerja dengan mengembalikan
fungsi termostat ke keadaan normal. Pembentukan
panas tidak dihambat tetapi hilangnya panas
dipermudah dengan bertambahnya aliran darah ke
perifer dan pengeluaran keringat. Efek penurunan
suhu demam diduga terjadi karena penghambatan
terbentuknya prostaglandin (Zubaidi, 1980).
Semua obat analgetik non opioid bekerja
melalui penghambatan siklooksigenase. Parasetamol
menghambat siklooksigenase sehingga konversi asam
arakhidonat menjadi prostaglandin terganggu.
Setiap obat menghambat siklooksigenase secara
berbeda. Parasetamol menghambat siklooksigenase
pusat lebih kuat dari pada aspirin, inilah yang
menyebabkan Parasetamol menjadi obat antipiretik
yang kuat melalui efek pada pusat pengaturan
28
panas. Parasetamol hanya mempunyai efek ringan
pada siklooksigenase perifer. Inilah yang
menyebabkan Parasetamol hanya menghilangkan atau
mengurangi rasa nyeri ringan sampai sedang.
Parasetamol tidak mempengaruhi nyeri yang
ditimbulkan efek langsung prostaglandin, ini
menunjukkan bahwa parasetamol menghambat sintesa
prostaglandin dan bukan blokade langsung
prostaglandin. Obat ini menekan efek zat pirogen
endogen dengan menghambat sintesa prostaglandin,
tetapi demam yang ditimbulkan akibat pemberian
prostaglandin tidak dipengaruhi, demikian pula
peningkatan suhu oleh sebab lain, seperti latihan
fisik. (Gunawan, 2007)
Parasetamol mempunyai daya kerja analgetik,
antipiretik, tidak mempunyai daya kerja anti
radang dan tidak menyebabkan iritasi serta
peradangan lambung. Hal ini disebabkan Parasetamol
bekerja pada tempat yang tidak terdapat peroksid
sedangkan pada tempat inflamasi terdapat lekosit
yang melepaskan peroksid sehingga efek anti
inflamasinya tidak bermakna. (Katzung, 2001)
3.Farmakokinetik
Parasetamol diabsorpsi dengan cepat dan
hamper sempurna dalam saluran cerna.
Konsentrasi dalam plasma mencapai puncak dalam
30 sampai 60 menit, waktu paruh dalam plasma
29
sekitar 2 jam. Indeks terapi parasetamol berada
diantara 5-20μg/ml. Parasetamol sedikit terikat
dengan protein plasma dan sebagian
dimetabolisme oleh enzim mikrosom hati.
Sebagian parasetamol (80%) dikonjugasi dengan
asam glukuronat dan sebagian kecillainnya
dengan asam sulfat, yang secara farmakologi
tidak aktif (Katzung,2001).
Kurang dari 5% parasetamol diekskresikan
dalam bentuk tidak berubah. Parasetamol
mengalami metabolism menghasilkan suatu
metabolit minor tetapi sangat aktif dan penting
pada dosis besar yaitu NAPQI karena toksik
terhadap hati dan ginjal. Pada jumlah toksik
atau adanya penyakit hati, waktu paruhnya
meningkat menjadi dua kali lipat atau lebih
(Katzung, 2001).
4.Indikasi
Parasetamol merupakan pilihan lini pertama
bagi penanganan demam dan nyeri sebagai
antipiretik dan analgetik. Parasetamol digunakan
bagi nyeri yang ringan sampai sedang (Gunawan,
2007).
5.Kontraindikasi
Penderita gangguan fungsi hati yang berat dan
penderita hipersensitif terhadap obat ini.
(Gunawan, 2007)
30
6.Efek Samping
Reaksi alergi terhadap derivate para-
aminofenol jarang terjadi. Manifestasinya berupa
eritem atau urtikaria dan gejala yang lebih berat
berupa demam dan lesi pada mukosa.
Fenasetin dapat menyebabkan anemia hemolitik,
terutama pada pemakaian kronik. Anemia hemolitik
dapat terjadi berdasarkan mekanisme autoimmune,
defisiensi enzim G6PD dan adanya metabolit yang
abnormal.
Methemoglobinemia dan Sulfhemoglobinemia jarng
menimbulkan masalah pada dosis terapi, karena
hanya kira-kira 1-3% Hb diubah menjadi met-Hb.
Methemoglobinemia baru merupakan masalah pada
takar lajak.
Insidens nefropati analgesik berbanding lurus
dengan penggunaan Fenasetin. Tetapi karena
Fenasetin jarang digunakan sebagai obat tunggal,
hubungan sebab akibat sukar disimpulkan.
Eksperimen pada hewan coba menunjukkan bahwa
gangguan ginjal lebih mudah terjadi akibat
Asetosal daripada Fenasetin. Penggunaan semua
jenis analgesik dosis besar secara menahun
terutama dalam kombinasi dapat menyebabkan
nefropati analgetik.
7.Sediaan dan Posologi
31
Parasetamol tersedi sebagai obat tunggal,
berbentuk tablet 500mg atau sirup yang mengandung
120mg/5ml. Selain itu Parasetamol terdapat sebagai
sediaan kombinasi tetap, dalam bentuk tablet
maupun cairan. Dosis Parasetamol untuk dewasa
300mg-1g per kali, dengan maksimum 4g per hari,
untuk anak 6-12 tahun: 150-300 mg/kali, dengan
maksimum 1,2g/hari. Untuk anak 1-6 tahun:
60mg/kali, pada keduanya diberikan maksimum 6 kali
sehari (Gunawan, 2007)
C. INTERAKSI OBAT
Pasien diberi terapi medikamentosa Parasetamol
500 mg dan Nalgestan 1 tablet yang dicampur dan
dijadikan satu dalam wadah kapsul. Tiap tablet
Nalgestan mengandung fenilpropanolamin hidroklorida
15 mg dan chlorpheniramine maleat 2 mg. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa jika parasetamol dan
fenilpropanolamin hidroklorida diberikan bersama
maka kadar puncak dalam plasma kedua obat tersebut
lebih kecil, sedangkan t1/2β fenilpropanolamin
hidroklorida lebih besar dari pada jika diberikan
secara tersendiri (Rusdiana dkk, 2012).
32
DAFTAR PUSTAKA
Adams GL, Boies LR, Higler PH (2007). Buku ajar penyakit THT.Edisi VI. Jakarta: EGC.
Darsono L (2002). Diagnosis dan terapi intoksikasi salisilat dan parasetamol. http://cls.maranatha.edu. Diakses tanggal 16 Juli 2014.
Dhingran PL (2007) Disease of ear nose and throat. 4th Ed. New Delhi, India: Elsevier.
Katzung BG (2001). Farmakologi dasar dan klinik. Buku1. Jakarta : Salemba Medika.
McEvoy A dan Gerald K (2002). AHFS Drug Book 4,American Society of Health System Pharmacist.
Moore KL, Anne AMR (2003). Anatomi klinis dasar. Jakarta: Hipokrates.
Rolla LT (2009). Acute rhinitis. The eclectic practice of medicine. Henriette’s Herbal.
Rusdiana T, Sjuib F, Asyarie S. 2012. Interaksi farmakokinetik kombinasi obat parasetamol dan fenilpropanolamin hidroklorida sebagai komponen obat flu. Bandung: Unpad.
Sobol SE (2007). Sinusitis acute medical treatment. http://www.emedicine.com/ ent/topic377.htm. Diaksestanggal 16 Juli 2014.
Soepardi EA (2007). Buku ajar ilmu penyakit telinga, hidung, tenggorokkan, kepala, leher. Edisi VI. Jakarta : FK UI.
33