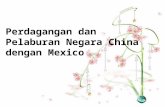LITBANG PERDAGANGAN
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of LITBANG PERDAGANGAN
Terakreditasi CBerdasarkan SK. Kepala LIPI No. 629/D/2011
(381/AU1/P2MBI/07/2011)Diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan
Kementerian Perdagangan
PENGARAHDrs. Herry Soetanto
PENANGGUNG JAWABKetua : Dr. Arief Adang, M.ScWakil Ketua : Ir. Marthin, MA
DEWAN REDAKSI/EDITORKetua : Ir. Tjahya Widayanti, M.Sc
Wakil Ketua : Ir. Kasan, MM
Anggota :Dr. Masyhuri Ph.D, APU
Dr. Wayan R. Susila, APUZamroni Salim, Ph.D
Redaksi Pelaksana :Adi Nurjaman, SE, MM
Maulida Lestari, SE, MEUlfah Anjarwati, BBANeneng Uliyah, SE
ALAMAT REDAKSISekretariat Badan Pengkajian dan
Pengembangan Kebijakan PerdaganganKementerian Perdagangan RI
Gedung Utama Lantai 4Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5
Tlp. (021) 23528681Fax. (021) 23528691Jakarta Pusat - 10110
Pengantar Redaksi
Badan Pengkajian dan Pengem-bangan Kebijakan Perdagangan (BP2KP) memiliki visi menjadi unit pengkaji yang terpercaya dan proaktif di bidang perdagangan. BP2KP berkomitmen untuk men-dukung sektor perdagangan se-bagai penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi melalui pengkajian dan pengembangan ke-bijakan yang berkualitas.
Buletin Ilmiah Litbang Perdagang-an yang terbit setiap semesternya merupakan salah satu media bagi BP2KP untuk menyebarluaskan hasil kajian/analisis yang telah dilakukannya kepada seluruh stakeholder.
Masukan dan kritikan yang mem-bangun menjadi salah satu alat evaluasi guna menjadikan buletin ilmiah ini menjadi lebih berkuali-tas dan bermanfaat, sehingga kami mengundang Saudara memberikan komentar yang ditujukan pada Sekretariat BP2KP.
ISSN : 1979 - 9187
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011
BULETIN ILMIAHLITBANG PERDAGANGAN
VOL. 5 NO. 2 DESEMBER 2011
BULETIN ILMIAHLITBANG PERDAGANGAN
VOL. 5 NO. 2 DESEMBER 2011
DAFTAR ISI
DAMPAK LIBERALISASI PERDAGANGAN SEKTOR PERTANIAN TERHADAP MAKRO DAN SEKTORAL EKONOMI INDONESIA: PENDEKATAN MODEL EKONOMI KESEIMBANGAN UMUM ....................Oleh : Kasan
DAMPAK LIBERALISASI WTO TERHADAP KETAHANAN PANGAN BERAS DAN GULA ......................................................................................Oleh : Adrian D. Lubis dan Reni K. Arianti
The COmpeTITIveness Of InDOnesIAn pRODuCT In TRADe ReLATIOnshIp wITh ChInA ......................................................................Oleh : umar fakhrudin
PENERAPAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK (sTRICT LIABILITy) DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN .......................................Oleh : yudha hadian nur dan Dwi wahyuniarti prabowo
PENGEMBANGAN SUSU SEGAR DALAM NEGERI UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN SUSU NASIONAL ..................................................................Oleh : heny sukesi dan miftah farid
DAMPAK PENERAPAN H.R.4380, The u.s. mAnufACTuRIng enhAnCemenT ACT Of 2010 BAGI INDONESIA .....................................Oleh : Aziza Rahmaniar salam
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011
123
148
164
177
196
222
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011 - 123
PENDAHULUANSaat ini isu liberalisasi perdagangan
khususnya komoditas pertanian terus menjadi perdebatan dan semakin jauh dari tercapainya kesepakatan dalam sistem perdagangan multilateral. Libe-ralisasi perdagangan sektor pertanian (kerangka multilateral/WTO) akan mempengaruhi pola perdagangan komoditas pertanian di berbagai kawasan.
Sementara itu, melambatnya laju pertumbuhan produksi pertanian atau bahkan penurunan produksi pertanian akan berdampak pada menurunnya
1 Mahasiswa S3 Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian IPB; dan Kepala Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, BPPKP-Kementerian Perdagangan Jl MI Ridwan Rais No. 5 Jakarta. E-mail: [email protected] atau [email protected]; Fax : 021-23528693
DAMPAK LIBERALISASI PERDAGANGAN SEKTOR PERTANIAN TERHADAP MAKRO DAN SEKTORAL EKONOMI INDONESIA:
PENDEKATAN MODEL EKONOMI KESEIMBANGAN UMUM
Oleh : Kasan1
Naskah diterima : 7 November 2011Disetujui diterbitkan : 10 Desember 2011
ABSTRACTRecently, trade liberalization issue particularly in agriculture sector has become the main issue in Doha Development Agenda-WTO. Trade liberalization in agriculture sector affected trade flow of primary agriculture products in global market particularly from developing countries to developed countries. This study analyzes the impact of trade liberalization in agriculture sector on macro and economic sectors of Indonesia, using general equilibrium economic model approach by employing GTAP model. It uses the data from the GTAP Version7. The main results show that trade liberalization in agriculture sector benefited developed countries such as the United States of America, Rusia, and European Union. On the other hand, some developing countries such as Pakistan, Bangladesh, and Indonesia were negatively affected. Furthermore, trade liberalization in agriculture sector reduced output of agriculture sector in Indonesia. Nevertheless, the output of manufacturing sector increased because of reallocation of input factor from agriculture to manufacturing.
Key words: Trade liberalization, general equilibrium, agriculture sector.
JEL Classification : F15, F17
pasokan, yang kemudian menyebabkan kenaikan harga. Selanjutnya jika per-mintaan tetap atau bahkan meningkat, maka kelebihan permintaan dapat dipenuhi melalui perdagangan (impor) produk pertanian dari sumber lain (negara lain). Hal ini berarti bahwa penurunan produksi pertanian akan mempengaruhi perdagangan (ekspor/impor) produk pertanian tersebut.
Di tingkat nasional, berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2009, selama periode 2004-2009 nilai dan volume ekspor beberapa produk pertanian mengalami penurunan. Nilai
124 - Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011
ekspor produk kehutanan mengalami penurunan rata-rata 5,3persen per tahun, sedangkan volume ekspornya turun lebih dari dua kali lipat yaitu mencapai 12,5 persen per tahun selama periode 2004-2009. Sementara itu, dalam periode yang sama nilai eskpor produk tanaman pangan dan hortikultura masih meningkat rata-rata 6,2 persen per tahun, walaupun volume ekspornya turun rata-rata 2,6 persen per tahun.
Kondisi yang sama dengan produk tanaman pangan dan hortikultura juga terjadi pada produk perikanan dan peternakan, yaitu nilai ekspornya naik rata-rata 5,1 persen per tahun, tetapi volume ekspornya turun rata-rata 1,7 persen per tahun. Peningkatan nilai ekspor produk tanaman pangan dan hortikultura, dan produk perikanan dan peternakan tersebut didukung oleh terjadinya peningkatan harga di pasar internasional.
Sementara itu, di tingkat global, selama 1961-2008, secara umum defisit neraca perdagangan produk pertanian dunia mengalami kenaikan , terutama gandum dan jagung sebagaimana terlihat pada Gambar 1 dan 2. Pada
tahun 1992, misalnya, defisit neraca perdagangan produk pertanian dunia menaik mendekati US$ 30 milyar, akan tetapi lima tahun kemudian mengecil sehingga menjadi sekitar US$ 10 milyar pada tahun 1997. Namun, sepuluh tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2008 disaat terjadinya krisisi ekonomi global, defisit neraca perdagangan produk pertanian dunia mencapai ke tingkat tertinggi yakni sekitar US$ 55 milyar.
Akan tetapi, kondisi yang dialami Indonesia berlawanan dengan yang terjadi dalam skala global, dimana selama periode 1961-2001 neraca perdagangan produk pertanian Indonesia masih mencatat surplus meskipun relatif stagnan (Gambar 1). Selanjutnya sejak tahun 2001, neraca perdagangan produk pertanian Indonesia terus meningkat dan mencapai tingkat tertinggi pada tahun 2008, disaat negara-negara lain di dunia justru mengalami krisis pangan. Tingginya surplus neraca produk pertanian Indonesia selama tahun 2000-an didukung terutama oleh peningkatan produksi minyak sawit yang juga merupakan produk ekspor utama Indonesia.
Gambar 1. Neraca Perdagangan Produk-Produk Pertanian Dunia dan Indonesia, 1961-2008
Dunia
Indonesia
-50,0
-40,0
-30,0
-20,0
-10,0
0,0
10,0
20,0
30,0
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Milia
r US$
Neraca Perdagangan Produk-produk Pertanian Dunia dan Indonesia
-6.000.000
-5.000.000
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006
Ribu
US$
Neraca Perdagangan Gandum, Beras dan Jagung Dunia dan Indonesia
Neraca Gandum Dunia Neraca Beras DuniaNeraca Jagung Dunia Neraca Gandum IndonesiaNeraca Beras Indonesia Neraca Jagung Indonesia
Sumber: FAO
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011 - 125
Meskipun secara agregat neraca perdagangan produk pertanian Indonesia masih mencatat surplus selama 1961-2008, ternyata untuk tiga komoditi pangan yaitu beras, gandum dan jagung, Indonesia mencatat defisit sebagaimana yang terjadi di dunia (Gambar 2). Untuk ketiga produk pertanian tersebut, defisit neraca perdagangan Indonesia lebih tinggi dibandingkan defisit neraca perdagangan dunia. Hal ini disebabkan oleh relatif tingginya konsumsi per kapita Indonesia terutama beras dan gandum sehingga meskipun Indonesia mampu memproduksi beras dalam jumlah yang cukup besar, tetapi produksi tersebut belum dapat mencukupi seluruh kebutuhan dalam negeri.
Kinerja perdagangan komoditas pertanian baik dalam skala nasional maupun global juga dipengaruhi oleh adanya liberalisasi sektor pertanian yang disepakati oleh berbagai negara dalam kerangka multilateral, regional maupun bilateral. Dalam kerangka multilateral, Indonesia sebagai anggota WTO mendukung kebijakan perdagangan
global yang bebas dan adil, dimana tujuan jangka panjang dari WTO adalah meliberalkan perdagangan dunia melalui 3 pilar, yaitu perluasan akses pasar (market access), pengurangan dukungan domestik (domestic support) yang dapat mendistorsi pasar, dan pengurangan subsidi ekspor (export subsidy). Tujuan ini seharusnya mendatangkan manfaat bersama bagi seluruh negara di dunia. Namun faktanya, perdagangan internasional dan hasil perundingan sektor pertanian di WTO lebih banyak merugikan negara-negara sedang berkembang (Suryana, 2004).
Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan untuk menciptakan sistem perdagangan sektor pertanian yang adil dan berorientasi pasar antara lain:1. Negara-negara maju masih
tetap mempertahankan, bahkan meningkatkan dukungan domestik melalui subsidi kepada petaninya, terutama produsen pangan dan peternakan (Suryana, 2004). Data OECD (2002) yang dikutip
Dunia
Indonesia
-50,0
-40,0
-30,0
-20,0
-10,0
0,0
10,0
20,0
30,0
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Mili
ar U
S$
Neraca Perdagangan Produk-produk Pertanian Dunia dan Indonesia
-6.000.000
-5.000.000
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006
Ribu
US$
Neraca Perdagangan Gandum, Beras dan Jagung Dunia dan Indonesia
Neraca Gandum Dunia Neraca Beras DuniaNeraca Jagung Dunia Neraca Gandum IndonesiaNeraca Beras Indonesia Neraca Jagung Indonesia
Gambar 2. Neraca Perdagangan Beras, Gandum, dan Jagung Dunia dan Indonesia, 1961-2008
Sumber: FAO
126 - Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011
Simatupang (2004) menunjukkan bahwa nilai dukungan domestik dari kelompok negara OECD meningkat dari rata-rata US$ 236 milyar per tahun pada periode pra-WTO (1986-1988) menjadi US$ 248 milyar pada masa implementasi kesepakatan WTO (1999-2001). Sementara itu, Amerika Serikat dan Uni Eropa (European Union-EU) meningkatkan dukungan domestik mereka masing-masing sebesar 21 persen dan 5 persen pada periode yang sama. Subsidi yang besar dari negara-negara maju tersebut mengakibatkan persaingan tidak adil di pasar dunia.
2. Selain subsidi domestik, negara-negara maju juga memberikan subsidi ekspor yang besar untuk produk-produk pertanian mereka.. Kelompok negara EU memberikan tingkat subsidi tertinggi, yaitu mencapai US$ 23,2 milyar atau 90 persen dari total nilai subsidi seluruh anggota WTO pada kurun waktu 1995-1998 (Dixix, Josling and Blandford, 2001). Menurut Simatupang (2004), subsidi ekspor itu menyebabkan disparitas harga antara pasar dunia dan pasar domestik negara-negara maju, sehingga dapat dipandang sebagai instrumen untuk fasilitasi praktik dumping yang dilarang WTO.
3. Ketidakseimbangan tingkat pem-bangunan ekonomi, teknologi, ketrampilan SDM, dan infrastruktur antara negara maju dan negara berkembang menyebabkan ketidak-mampuan negara berkembang menciptakan kondisi persaingan seimbang (equal playing field) (Sawit, 2003). Di negara-negara berkembang pada umumnya,
dan Indonesia pada khususnya, karakteristik usaha pertanian umumnya masih bersifat subsisten, yaitu belum berorientasi komersial secara penuh. Artinya, pertanian masih menjadi perikehidupan dan kebudayaan masyarakat.. Kondisi yang demikian kurang selaras dengan aturan dalam Agreement of Agriculture (AoA) dan mekanisme pasar yang hanya sesuai bagi industri pertanian modern yang berorientasi pasar di negara-negara maju.
4. Ketidakadilan dalam membuka akses pasar, dimana di satu sisi negara maju memaksa negara berkembang untuk membuka akses pasar seluas-luasnya, sementara di sisi lain negara maju berusaha membatasi akses pasar bagi produk-produk negara berkembang melalui berbagai instrumen, seperti tarif eskalasi, perlindungan sanitary dan phyto-sanitary, dan non-trade barrier lainnya.
Perbedaan kepentingan dan kebijakan itulah yang menimbulkan kondisi perdagangan multilateral sektor pertanian yang tidak seimbang dan mengarah tidak adil (fair). Berbagai studi menunjukkan bahwa manfaat reformasi perdagangan global jauh lebih banyak dinikmati oleh negara-negara maju dibandingkan dengan negara berkembang (Sawit, 2003; Khor, 2000; dan Ellwood, 2002). Laporan UNDP (United Nation Development Program) tahun 1999 dalam Sawit (2001) menyebutkan perdagangan global membuat defisit perdagangan negara berkembang semakin lebar. Impor telah meningkat dengan pesat, sementara ekspor melambat karena tidak mampu bersaing dengan industri negara maju
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011 - 127
yang memberikan dukungan yang masih tinggi terhadap sektor industri mereka, baik melalui subsidi ekspor, bantuan domestik, maupun berbagai hambatan perdagangan lainnya.
Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperkirakan besaran dampak liberalisasi per-dagangan sektor pertanian terhadap kondisi makro ekonomi termasuk kinerja perdagangan negara-negara produsen serta terhadap importir komoditas pertanian di negara maju maupun di negara berkembang, termasuk Indonesia.
KERANGKA TEORITISTeori Perdagangan Internasional
Konsep perdagangan bebas yang menjadi ide dasar terbentuknya Free Trade Area (FTA), untuk pertama kali diperkenalkan oleh Adam Smith pada awal abad ke-19 dengan teori keunggulan absolut (absolute advantage). Teori Adam Smith ini kemudian disempurnakan oleh Ricardo (1817) dengan model keunggulan komparatif (the Theory of Comparative Advantage). Berbeda dengan konsep keunggulan absolut yang menekankan pada biaya riil yang lebih rendah, keunggulan komparatif lebih melihat pada perbedaan harga relatif antara dua input produksi sebagai penentu terjadinya perdagangan.
Teori klasik Ricardo tersebut selanjutnya dikembangkan oleh Heckscher-Ohlin (H-O) dengan the Theory of Factor Proportions (1949 – 1977) yang menyatakan bahwa walaupun tingkat teknologi yang dimiliki sama, perdagangan internasional akan tetap terjadi bila ada perbedaan kepemilikan faktor produksi (factor
endowment) diantara masing-masing negara. Satu negara dengan kepemilikan kapital berlebih akan berspesialisasi dan mengekspor komoditi padat kapital (capital-intensive goods), dan sebaliknya negara dengan kepemilikan tenaga kerja berlebih akan memproduksi dan mengekspor komoditi padat tenaga kerja (labor-intensive goods).
Selanjutnya seiring perubahan jaman konsep perdagangan internasional terus berkembang, namun masih tetap menggunakan konsep keunggulan komparatif yang dikembangkan sebelumnya. Krugman dan Obstfeld (2000), misalnya, menjelaskan bahwa perdagangan antar negara terjadi karena dua alasan, yaitu: (1) negara-negara tersebut berbeda satu sama lain, dan (2) negara-negara melakukan perdagangan dengan tujuan untuk mencapai skala ekonomi. Dengan demikian akan lebih efisien jika dilakukan perdagangan dengan negara lain dibandingkan jika negara itu memproduksi semua produk.
Sesuai dengan tujuan pene-litian, untuk bisa memahami manfaat yang dapat diperoleh dari adanya perdaganganmaka digunakan pendeka-tan perdagangan internasional dengan mengaplikasikan model ekonomi keseimbangan umum sebagaimana dijelaskan pada bagian di bawah ini.
Pendekatan Model Ekonomi Keseimbangan Umum
Secara sederhana teori keseimbangan umum dapat dijelaskan dengan menggunakan model “ekonomi dua pasar” (Salvatore, 2000). Dengan model ini dimisalkan, ketika pemerintah negara 1 menerapkan tarif terhadap produk yang selama ini diimpor yaitu X, akibatnya harga produk X akan meningkat relatif terhadap harga di pasar
128 - Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011
internasional. Sesuai dengan hukum penwaran, maka peningkatan harga X akan merangsang produsen domestik di negara 1 untuk meningkatkan produksinya, dan sebaliknya produksi Y akan menurun karena produsen doimestik akan merugi. Sesuai hukum permintaan dan penawaran tenaga kerja, maka dengan m,eningkatnya produksi X, maka akan diikuti oleh relokasi faktor produksi seperti tenaga kerja dari industri yang menghasilkan produk Y ke industri yang memproduksi X. Namun, dalam model partial equilibrium, proses terjadinya relokasi faktor input produksi tersebut tidak akan terdeteksi.
Contoh lain adalah ketika impor negara 1 menurun karena pengenaan tarif, maka negara lain yang menerima dampak penurunan impor negara 1 tersebut akan mengalami penurunan penerimaan sehingga kemampuan ekspornya juga akan turun. Hal ini akan mengakibatkan impor negara 1 tersebut juga turun. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa kebijakan tarif impor berdampak terhadap berbagai variabel ekonomi lainnya di negara lain. Namun, karena yang digunakan adalah model partial, maka dampak terhadap negara lain tersebut tidak akan terlihat. Oleh karena itu, agar dampak suatu kebija-kan yang diterapkan di suatu negara dapat ditangkap pengaruhnya terhadap negara lainnya, maka analisis yang tepat adalah analisis ekonomi keseimbangan umum.
Untuk menjelaskan analisis menggunakan model ekonomi kese-imbangan umum yang dicapai melalui perdagangan akan dijelaskan melalaui grafik berikut dengan mengacu pada teori Ekonomi Internasional yang dikemukakan Salvatore (2000). Berbeda dengan analisis partial, dalam
analisis model keseimbangan umum sudah merangkum aspek dari pelaku yaitu produsen dalam bentuk produksi, dan konsumen melalui konsumsi serta perdagangan, semua dirangkum dalam satu diagram yang utuh pada kondisi keseimbangan. Sisi produksi dari masing-masing negara 1 dan 2 digambarkan dalam satu titik yaitu E*,
dimana kurva yang menunjukkan adanya perdagangan atau tawar menawar antara kedua Negara tersebut saling berpotongan.
Sebagaimana pemahaman terhadap penggunaan konsep suatu teori yaitu untuk menyederhanakan suatu fenomena, maka untuk memudahkan analisis ini juga disederhanakan dengan menggunakan beberapa asumsi yaitu: 1) diasumsikan hanya terdapat dua Negara di dunia yaitu Negara 1 dan Negara 2 secara individu atau merupakan gabungan dari berbagai Negara; 2) diasumsikan juga bahwa hanya terdapat dua jenis produk yaitu X dan Y; 3) struktur pasar diasumsikan pada kondisi pasar persaingan sempurna: 4) Asumsi terakhir adalah perekonomian kedua negara berada dalam kondisi penggunaan tenaga kerja penuh atau full employment.
Setelah berlangsungnya perda-gangan antara Negara 1 dan Negara 2, maka kondisi produksi dan konsumsi terhadap barang X dan Y di masing-masing Negara dapat dijelaskan sebagai berikut. Untuk Negara 1 akan memproduksi barang X dan Y masing-masing sebanyak 130 dan 20 yang ditunjukan pada titik E yang juga identik dengan titik E*. Dengan memproduksi sejumlah barang X dan Y tersebut, maka Negara 1 akan mengkonsumsi barang X dan Y masing-masing sebanyak 70 dan 80 yang juga ditunjukkan pada
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011 - 129
titik E, tetapi ditarik dari garis sumbu O, sedangkan sisanya yaitu masing-masing sebanyak 60 unit X dan 60 unit Y akan diperdagangkan dengan Negara 2, yang berarti Negara 1 akan mengekspor barang X dan mengimpor barang Y.
Sementara itu, dengan cara yang sama, maka untuk Negara 2 akan memproduksi barang X dan Y masing-masing sebanyak 40 dan 120 yang ditunjukkan pada titik E’ yang juga identik dengan titik E*. Sedangkan konsumsinya masing-masing sebanyak 100 X dan 60Y yang juga ditunjukkan pada titik E’, tetapi ditarik terhadap garis sumbu O, sehingga sisanya yaitu masing-masing sebanyak 60 X akan diimpor dari Negara 1 dan sebanyak 60 Y akan diekspor ke Negara 1. Jumlah barang X dan Y tersebut adalah yang kemudian diperdagangkan oleh kedua Negara.
Perdagangan internasional antara kedua Negara akan mencapai keseimbangan apabila kedua Negara memperdagangkan masing-masing sebanyak 60X dan 60Y yang didasarkan pada harga relative kedua barang
tersebut yaitu ditunjukkan pada Pb=1 yang merupakan perpotongan kurva penawaran kedua Negara tersebut sebagaimana ditunjukkan pada titik E*. Harga relative kedua barang yaitu X dan Y terjadi dalam kondisi keseimbangan pada tingkat harga Pb =1, sehingga harga tersebut yang selanjutnya berlaku dalam transaksi perdagangan di pasar domestik bagi masing-masing Negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa transaksi perdagangan akan didasarkan pada harga relative yang sama bagi produsen, konsumen, dan pedagang di kedua Negara tersebut. Sebagaimana digambarkan pada grafik, titik E milik Negara 1 yang terletak pada kurva indeferen III akan mencerminkan jumlah tingkat konsumsi Negara tersebut diukur dari pusat sumbu atau titik 0, sementara untuk titik E yang sama akan mengukur jumlah produksi barang X dan Y Negara 1 tetapi ditarik dari titik E’.
Dengan mengacu pada penjelasan tersebut diatas, maka secara teori perdagangan bebas akan memberikan manfaat yang maksimal
Gambar 3. Proses Terjadinya Perdagangan Antara Dua Negara
Sumber: Salvatore, 2000.
130 - Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011
bagi kedua belah pihak (Negara 1 dan 2). Namun demikian, pada kenyataanya masih terjadi distorsi pasar sebagai akibat adanya campur tangan atau intervensi pemerintah, sehingga berakibat pada tidak tidak maksimalnya manfaat yang diperoleh oleh pelaku pasar yaitu produsen, konsumen bahkan pemerintah itu sendiri. Sampai saat ini berbagai bentuk interventi pemerintah yang sering dilakukan baik di Negara maju maupun di Negara berkembang antara lain pengenaan tariff bea masuk, subsi terhadap produk ekspor, larangan atau pembatasan ekspor maupun impor dan berbagai bentuk intervensi lainnya yang semuanya berdampak pada munculnya distorsi pasar.
Pendekatan model ekonomi keseimbangan umum yang digunakan dalam penelitian ini, bukanlah model yang baru muncul, tetapi sudah digunakan untuk melakukan analisis perubahan kebijakan ekonomi makro maupun sektoral di berbagai negara. Pengembangan model ekonomi keseimbangan umum juga telah digunakan untuk menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Yeah et. al (1994) menyatakan bahwa model ekonomi keseimbangan umum menyediakan mekanisme untuk menganalisis dampak kebijakan perdagangan suatu negara dan dampak liberalisasi oleh kelompok negara. Buehrer dan Mauro (1995) juga menegaskan bahwa model ekonomi keseimbangan umum dapat digunakan untuk menyimulasi dampak dari kebijakan perdagangan dan dampak perubahan ekonomi dari berbagai paket kebijakan pemerintah.
Dalam penelitian ini digunakan model Global Trade Analysis Project (GTAP) dengan data sekunder berupa
data base GTAP versi 7 dengan basis data tahun 2004. GTAP dikembangkan pertama kali di Purdue Univrsity, pada Departemen Ekonomi Pertanian di Amerika Serikat sejak tahun 1993 yang dipimpin dan diprakarsai oleh Prof Thomas W. Hertel dalam sebuah konsorsisum. Pemodelan dan aplikasi mengenai GTAP ditulis oleh Thomas W Hertel dan dipublikasikan oleh Cambridge University Press.New York USA tahun 1997 berjudul “ Global Trade Analysis: Modelling and Applications”. Konsorsium tersebut bersifat non profit, dimana pembiayaannya bersumber dari penjualan database, pelatihan dan anggota konsorsium. Sejak dikembangkan pertama kali tahun 1993, telah dikeluarkan beberapa versi model GTAP diantaranya 2 versi terakhir adalah versi 6.2 yang dikeluarkan tahun 2007 dengan database terdiri dari 87 negara (region) dan 57 komoditi (sector) dengan menggunakan data dasar tahun 2011. Kemudian pada tahun 2008 dirilis model GTAP versi 7 yang mencakup 113 negara (region) dan 57 komoditi (sector) dengan menggunakan data dasar tahun 2004 (www.gtap.agecon.purdue.edu, 2011).
Menurut Oktaviani , 2008, GTAP merupakan model keseimbangan umum (CGE) yang memfokuskan pada aspek perdagangan internasional dengan tidak mengesampingkan ekonomi mikro dan makro dari Negara-negara di dunia. Penekanana GTAP terletak pada keterkaitan perekonomian secara keseluruhan.
Lebih lanjut Oktaviani (2008), menjelaskan bahwa sampai saat ini model GTAP terus mengalami pengembangan, baik dari sisi database
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011 - 131
maupun model yang digunakan. Model yang berkembang saat ini adalah masih model GTAP standar. Namun demikian, Konsorsium GTAP saat ini tengah mengembangkan model GTAP Dinamis (GTAP-Dyn). Model ini telah memasukkan aspek-aspek dinamis, seperti permintaan konsumen, mobilitas factor antar sector, perilaku investasi, dan hubungan pehitungan yang menangkap modal dari kepemilikan asing.
Di Indonesia penggunaan pendekatan model ekonomi kese-imbangan umum mulai populer sejak diskusi terbuka mengenai metode perhitungan dampak kemiskinan akibat kenaikan harga bahan bakar minyak dimuat di harian Kompas pada awal tahun 2005. Bahkan, sebelumnya di Indonesia telah dikembangkan model ekonomi keseimbangan umum dengan mengadopsi model yang telah ada seperti ORANI (Dixon et. al. 1982), ORANI-F (Horridge et. al. 1993), ORANI –G (Horridge, 2000) dan ORANI-GRD (Horridge, 2002) dari Australia dan model Lewis dari Amerika Serikat.
Sampai saat ini, beberapa penelitian di Indonesia juga telah banyak menggunakan pendekatan model ekonomi keseimbangan umum sebagai alat analisis. Misalnya, Rina Oktavianai et. al. (2003), melakukan studi mengenai “Dampak restrukturisasi perbankan terhadap kinerja ekonomi makro dan sektor pertanian” di Indonesia. Studi lainnya yang juga dilakukan oleh Rina Oktaviani et. al (2005) adalah “Peranan fasilitas pembiayaan ekspor terhadap perekonomian Indonesia”. Rina Oktaviani et. al (2006) juga melakukan “Analisis dampak perubahan variabel makro ekonomi terhadap sektor industri”.
SUMBER DATA DAN METODOLOGI
Sumber dan Jenis Data serta Keterbatasan Model Ekonomi Keseimbangan Umum
Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data base GTAP versi 7 dengan basis data tahun 2004. Data sekunder di atas digunakan sebagai policy shock dalam model GTAP untuk menganalisis dampak liberalisasi sektor pertanian dalam kerangka WTO. Keterbatasan penggunaan model ekonomi keseimbangan umum sebagaimana dikemukakan Rina Oktaviani (2008) yaitu : 1) Asumsi utama dalam model ekonomi keseimbangan umum mengenai struktur pasar adalah Pasar Persaingan Sempurna dengan kondisi Constant Return to Scale; 2) Adanya ketergantungan model keseimbangan pada parameter-parameter benchmark yang dikalibrasi; 3) Model ekonomi keseimbangan umum (Computable General Equilibrium- CGE) ini terlalu kompleks dan terlalu banyak asumsi yang digunakan, sehingga akan muncul permasalahan black box, sehingga sulit untuk menerangkan jika hasil estimasi yang didapat tidak sesuai dengan teori ekonomi atau prediksi yang diharapkan; 4) Pada model CGE tidak ada validitas terhadap hasil pengolahan, sehingga bagi orang-orang yang mengutamakan keabsahan dalam model merasa akan sangat riskan menggunakan model CGE; dan 5) Model CGE tidak menangkap perubahan perekonomian yang sangat besar (tidak dapat menganalisis perubahan persentase lebih dari 100 persen).
132 - Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011
Kerangka Pemikiran dan Tahapan Penelitian
Kerangka pemikiran analisis dampak liberalisasi perdagangan sektor pertanian terhadap makro dan sektoral ekonomi Indonesia disusun dengan skema sebagaimana disajikan pada Gambar 4. Liberalisasi perdagangan pada sektor pertanian di berbagai negara diasumsikan terjadi melalui penurunan tarif bea masuk dalam kerangka WTO. Selanjutnya analisis dampak dari penurunan tarif bea masuk ini terhadap perubahan variabel makro ekonomi serta terhadap sektoral ekonomi Indonesia dilakukan dengan menggunakan pendekatan model ekonomi keseimbangan umum (dengan menggunakan model software GTAP).
Simulasi dampak liberalisasi perdagangan sektor pertanian terhadap kondisi makro di negara produsen dan importir secara umum, serta secara khusus terhadap sektoral ekonomi Indonesia, dilakukan dalam dua bentuk simulasi kebijakan. Simulasi pertama dilakukan dengan penurunan tarif bea masuk sektor pertanian di negara berkembang dan negara maju masing-masing sebesar 36% dan 70% (simulasi 2). Simulasi kedua adalah penurunan tarif bea masuk sektor pertanian baik di negara berkembang maupun di negara maju secara penuh atau penurunan tariff
sebesar 100% (simulasi 3). Untuk melakukan kedua simulasi
tersebut, terlebih dahulu dilakukan agregasi sektor dan negara (region) pada data base GTAP versi 7 menjadi 19 sektor dan 14 negara (region). Penetapan agregasi sektor didasarkan pada pertimbangan jenis komoditas pertanian yang diperkirakan cukup signifikan dilihat dari sisi produksi, ekspor maupun impor di pasar global. Sedangkan untuk agregasi negara (region) mempertimbangkan posisi sebagai negara produsen maupun importir utama komoditas pertanian.
Setelah agregasi sektor dan negara dilakukan, maka tahap berikutnya adalah melakukan pengolahan data (run GTAP ) pada kedua simulasi kebijakan yang telah ditetapkan. Selanjutnya hasil dari masing-masing simulasi kebijakan tersebut dianalisis, terutama mengenai dampak kedua simulasi tersebut terhadap kondisi makro ekonomi negara produsen dan importir komoditas pertanian. Selain itu, secara khusus dianalisis juga dampak simulasi terhadap sektoral ekonomi Indonesia. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dirumuskan beberapa kesimpulan yang merupakan temuan utama dari penelitian ini. Dari beberapa kesimpulan utama tersebut, kemudian dirumuskan implikasi kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah.
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011 - 133
Ruang Lingkup Dalam pelaksanaan penelitian
ini, maka ruang lingkup dibatasi pada aspek-aspek sebagai berikut: 1. Liberalisasi perdagangan yang
dimaksudkan dalam penelitian ini adalah skema penurunan tarif yang diterapkan pada sektor pertanian termasuk komoditas pangan (beras, gandum, dan jagung) dalam kerangka multilateral-WTO.
2. Negara yang dimaksudkan dalam penelitian ini mencakup negara produsen utama komoditas beras, gandum dan jagung yaitu Amerika Serikat, China, Brazil, Filipina, India, Rusia, EU, Indonesia, Vietnam, Thailand, Australia, Pakistan, Bangladesh, dan Rest of the World (ROW).
3. Aspek makro meliputi dampak pada kesejahteraan (variabel equivalent
Gambar 4. Kerangka Pemikiran
134 - Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011
variation) (, Produk Domestik Bruto (PDB) riil, PDB deflator, trade balance, terms of trade, investasi, konsumsi rumah tangga, dan pengeluaran pemerintah.
4. Secara sektoral yang akan dianalisis adalah output, harga, ekspor, impor dan kesempatan kerja di Indonesia.
5. Analisis menggunakan software model GTAP versi 7 yang dikeluarkan pada tahun 2008 dengan data dasar tahun 2004 yang diagregasi ke dalam 19 sektor dan 14 negara (region). Agregasi sektor dan negara secara lengkap sebagaimana disajikan pada table 1 berikut.
Tabel 1. Agregasi Sektor dan Negara
Sumber: GTAP Database Versi 7
No. Sektor No Negara/Wilayah 1 Rice 1 Australia2 Wheat 2 Rusia3 Cereal grains nec (Maize) 3 China4 Vegetables, fruit, nuts 4 Indonesia5 Oilseed 5 Thailand6 Sugar cane, sugar beet 6 Vietnam7 Cattle,sheep,goats,horses 7 India8 Raw milk 8 United States of America 9 Forestry 9 Brazil10 Fishing 10 Philipina11 Other Agriculture 11 EU12 Meat: cattle,sheep,goats,horse 12 Pakistan13 Vegetable oils and fats 13 Bangladesh14 Sugar 14 RestofWorld15 Food and Beverage16 Leather products17 Mining, Oil,and Gas18 Manufacturing products19 Services
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011 - 135
Alat dan Prosedur AnalisisAlat analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah model ekonomi keseimbangan umum atau biasa disebut juga CGE. Model struktural CGE dibangun dengan dasar-dasar teori ilmu mikroekonomi dimana tingkah laku agen-agen ekonomi dijelaskan secara spesifik dan detail dalam bentuk sistem persamaan (behavioral equation). Oleh karena itu, CGE dapat menggambarkan interaksi antara agen-agen (pelaku-pelaku ekonomi) yang berbeda di dalam suatu negara/wilayah dan antar negara/wilayah.
Model CGE dapat menganalisis pasar secara lengkap dan saling berinteraksi satu sama lain. Model ekonomi ini dapat menganalisis variabel-variabel makro ekonomi dan sektoral secara bersama-sama terhadap perubahan kebijakan perekonomian pada tingkat makro maupun sektoral. Model ini juga menganalisis sensitivitas dari alokasi sumberdaya karena adanya perubahan eksternal. Selain itu, data yang digunakan dalam model CGE meliputi parameter elastisitas dan input-output data yang menunjukkan keterkaitan antar sektor sehingga model CGE dapat digunakan sebagai alat analisis terhadap perubahan sektoral.
Salah satu alat analisis (software) yang menyediakan model dan data dasar untuk model ekonomi keseimbangan umum yang dapat menangkap dampak perubahan ekonomi di suatu negara atau suatu kawasan terhadap perekonomian global dan ekonomi negara yang bersangkutan adalah model GTAP.. Model GTAP memfokuskan pada aspek perdagangan internasional dengan tidak mengesampingkan ekonomi mikro dan makro dari negara-negara di dunia. Model software GTAP yang digunakan
adalah versi terakhir yaitu versi 7 yang dikeluarkan pada tahun 2008.
Baik model GTAP maupun model CGE sama-sama menggunakan konsep dasar pengeluaran dan pembelian antar pelaku ekonomi. Keduanya merupakan model struktural yang dibangun dengan dasar teori-teori mikroekonomi dengan menjelaskan lebih detil perilaku-perilaku di masing-masing agen ekonomi (behavioral parameters).
Di dalam model GTAP dijelaskan interaksi perdagangan antar wilayah serta transportasi global dan mobilitas investasi. Melalui model ini dapat dijelaskan pula bagaimana pengaruh kebijakan yang dilakukan suatu negara/wilayah akan memberikan dampak kepada negara/wilayah lain.
HASIL DAN PEMBAHASANDampak Liberalisasi Perdagangan Sektor Pertanian terhadap Kondisi Makro Ekonomi di Negara Produsen dan Importir Komoditas Pertanian
Walaupun, berdasarkan teori ekonomi, perdagangan tanpa hambatan tarif dan non-tarif akan meningkatkan kesejahteraan dua negara yang mengadakan pertukaran barang, masih banyak negara yang dengan alasan ekonomi maupun non-ekonomi melakukan hambatan tersebut. Alasan ekonomi ditujukan untuk melindungi industri yang baru berdiri (infant industry argument) dan sumber pemasukan negara serta menggairahkan produsen dalam negeri. Sedangkan alasan non-ekonomi biasanya adalah antara lain alasan keamanan, keamanan pangan, kebudayaan dan kesehatan. Menurut tinjauan teoritis, pengenaan tarif akan merugikan konsumen domestik, menguntungkan produsen domestik dan negara, serta merugikan masyarakat.
136 - Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011
Dengan demikian, penurunan tingkat tarif diharapkan dapat mengurangi kerugian yang ditimbulkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Perubahan kinerja ekonomi makro di negara produsen dan importir komoditas pertanian sebagai dampak dari liberalisasi perdagangan sektor pertanian dijelaskan pada bagian ini dengan mengacu pada tabel 3.
Tabel 3 menunjukkan bahwa seluruh negara, baik yang diklasi-fikasikan sebagai negara maju maupun berkembang, diprediksi hanya akan mengalami peningkatan PDB rill yang relatif kecil, kurang dari satu persen baik dalam t skenario liberalisasi perdagangan komoditas pertanian sebesar 70 persen untuk negara maju dan 36 persen bagi negara berkembang (Skenario 2) maupun dalam scenario full liberalization sektor pertanian dengan besaran 100 persen (Skenario 3). Dampak liberalisasi perdagangan sektor pertanian secara penuh menunjukkan bahwa arah dan pergerakan magnifikasi intensitas liberalisasi perdagangan dari skenario 2 ke 3 menyebabkan perubahan PDB yang positif bagi negara berkembang seperti China, Indonesia, Filipina, Pakistan, Thailand, Vietnam, India, dan Bangladesh. Fenomena yang identik dalam peningkatan PDB juga terlihat bagi EU dan Rusia yang tergabung dalam negara maju. Lebih lanjut, analisis menunjukkan bahwa penurunan tarif menguntungkan negara maju seperti Amerika Serikat, Rusia, dan EU karena menurunkan PDB deflator atau menurunkan tingkat inflasi
di wilayah tersebut (Tabel 3). Penurunan tingkat tarif pada komoditas pertanian juga berpengaruh nyata terhadap indeks harga umum negara tersebut. Dampak penurunan tarif terhadap perubahan PDB deflator yang juga tinggi adalah di EU-252 dan Rusia yang telah menerapkan tarif impor yang tinggi pada komoditas pertanian. Dampak dari penurunan tarif pada perubahan PDB deflator paling tinggi terjadi di Indonesia, Pakistan, dan Bangladesh yang menerapkan tarif yang tinggi pada komoditas pertanian.
Australia yang termasuk negara maju terkena dampak penurunan tarif impor yang berbeda dengan negara maju lainnya. Negara tersebut adalah negara pengekspor komoditas pertanian terutama gandum dan produk peternakan dan memiliki tingkat tarif impor yang paling rendah dibandingkan negara maju lainnya. Dampak penurunan tarif terhadap kedua negara tersebut justru meningkatkan PDB deflator. Hal ini bisa terjadi karena adanya peningkatan ekspor pertanian kedua negara tersebut ke negara maju yang disebabkan oleh penurunan tarif di negara maju yang dapat dilihat dari perubahan nilai Terms of Trade (TOT) yang positif. Peningkatan ekspor mengakibatkan kelangkaan penawaran di pasar domestik dan meningkatkan harga di pasar domestik. Hal ini akan meningkatkan indeks harga umum dan secara langsung akan meningkatkan PDB deflator.
Selanjutnya, dampak penurunan tariff juga dianaliis terhadap tingkat kesejahteraan (Equivalent Variation/EV), dimana dalam model GTAP tingkat
2 EU-25 mencakup : Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Sweden, United Kingdom, Germany, France, Switzerland, Norway
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011 - 137
kesejahteraan didefinisikan sebagai perbedaan antara tingkat pengeluaran (expenditure) yang diperlukan untuk mencapai tingkat kepuasan yang baru (post simulation) pada tingkat harga tertentu atau dinotasikan (YEV) dengan tingkat kepuasan yang ada (available initially) atau disimbolkan Y. Secara matematis tingkat kesejahteraan atau equivalent variation di dalam model GTAP diformulasikan sebagai : EV = YEV – Y(1). Lebih lanjut dijelaskan bahwa model GTAP menggambarkan perilaku rumah tangga regional (Negara) yang disusun dalam bentuk suatu fungsi kepuasan (utility) secara agregat yang dispesifikasi dalam bentuk konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran pemerintah per kapita, dan tabungan per kapita.
Selanjutnya dalam GTAP model perdagangan multiregion, dekomposisi dari tingkat kesejahteraan (EV) adalah sama dengan pendekatan model single region. Perbedaannya terletak pada adanya beberapa variabel yang ada dalam model yaitu persentase pajak (tariff) dalam perdagangan baik tariff impor maupun tariff ekspor, dan terminologi untuk menangkap dampak perubahan dalam perdagangan regional. Perbedaan yang signifikan lainnya adalah tambahan dimensi dekomposisi regional yang mencakup tiga terminologi yaitu region (Negara), komoditi yang diperdagangkan dan margin dari komoditi.
Fenomena anomali dampak penurunan tariff sektor pertanian bagi kesejahteraan terlihat hanya di Indonesia dan China (dan Bangladesh dalam skenario 2) yang merupakan negara pengekspor sekaligus pengimpor produk pertanian (Tabel 3). Respon kesejahteraan negatif tersebut
merupakan suatu peringatan bahwa manfaat liberalisasi perdagangan bagi Indonesia dan China dalam skala makroekonomi tidak sepenuhnya dapat ditransmisikan bagi kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, preseden negatif kinerja perdagangan ditunjukkan dengan nilai yang negatif pada neraca perdagangan Rusia, EU-25, China, Brazil, Indonesia, Philipina dan Bangladesh pada kedua skenario liberalisasi perdagangan. Untuk kasus Indonesia, isu sentral yang harus dicermati mengenai kinerja perdagangan adalah sejauh mana kekuatan penawaran ekspor Indonesia dapat merespon peluang liberalisasi perdagangan. Prediksi menunjukkan bahwa kebijakan liberalisasi baik dalam bentuk tarif (pajak ekspor dan tarif impor) berpotensi untuk meningkatkan laju pertumbuhan impor lebih cepat daripada ekspor. Hal ini terjadi di Rusia, China, Indonesia, Philipina, Brazil dan ROW pada skenario 2 dan 3, serta di EU-25 pada skenario 2 (Tabel 3).
Namun demikian, pada beberapa negara, seperti Australia, Pakistan, Thailand, Vietnam, India, Bangladesh, dan Amerika Serikat, terlihat bahwa liberalisasi perdagangan memberikan insentif peningkatan ekspor lebih besar daripada impor.. Realitas menunjukkan bahwa lebih mudah bagi importir untuk langsung melakukan impor dibanding eksportir merelokasi sumber daya atau faktor produksi untuk mengekspor.
Sesungguhnya fenomena yang terjadi pada kinerja ekspor Indonesia adalah kendala dari sisi penawaran. Kondisi ini akan semakin buruk jika perdagangan bebas tidak memberikan insentif dan tidak mendorong terciptanya strategi jangka panjang bagi industri
138 - Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011
untuk meningkatkan produktivitas melalui efisiensi produksi maupun adopsi teknologi. Peningkatan kualitas infrastruktur ekspor, seperti peningkatan kualitas pasca panen, pengemasan dan penanganan pasca panen serta penguatan laboratorium uji mutu akan meningkatkan daya saing ekspor Indonesia untuk menembus pasar ekspor global. Peningkatan efisiensi manajemen rantai penawaran juga diperlukan agar produk Indonesia dapat menembus akses pasar di negara tujuan ekspor dengan lebih efisien (Oktaviani et. al, 2010).
Secara umum, proksi variabel konsumsi riil rumahtangga agregat yang menunjukkan kemampuan daya beli masyarakat meningkat terlihat untuk Australia dan Brazil, meskipun dengan intensitas yang sangat kecil. Peningkatan konsumsi rumahtangga terjadi karena konsumen memperoleh barang dengan harga yang relatif murah sebagai dampak adanya trade creation effect. Dibukanya potensi perdagangan menstimulasi terjadinya consumption effect dimana secara grafis, garis Consumption Possibility Frontier (CPF) akan meningkat ke atas. Ini berarti bahwa adanya perdagangan melalui penurunan tarif membuat masyarakat bisa mengonsumsi dalam jumlah yang lebih besar. Dengan kata lain bahwa pendapatan riil masyarakat (yaitu pendapatan yang diukur dari berapa jumlah barang yang bisa dibeli dengan pendapatan tersebut) meningkat dengan adanya penurunan tarif. Sementara itu, hampir keseluruhan negara berkembang kecuali Thailand dan Vietnam pada
kedua skenario dan India pada skenario 2 serta negara maju seperti AS dan EU-25 cenderung mengalami penurunan konsumsi rumahtangga pertanian.3 Kondisi ini serupa dengan konsumsi yang dilakukan oleh pemerintah.
Sementara itu, keterkaitan positif antara liberalisisasi perdagangan sector pertanian dan investasi terjadi pada China, Philipina, Bangladesh, Brazil dan ROW pada skenario 2 dan 3, sedangkan untuk EU-25 hanya pada skenario 2 (Tabel 3). Skema liberalisasi perdagangan secara komprehensif telah menyediakan ruang untuk peningkatan investasi. Persetujuan untuk meliberalisasi perdagangan di sektor barang dan jasa akan mendorong dunia usaha untuk menyesuaikan dengan lingkungan bisnis bilateral tanpa hambatan. Daya tarik bagi investasi akan menjadi semakin tinggi dengan adanya reformasi regulasi, minimisasi resiko ketidakpastian dalam berusaha, dan perbaikan iklim investasi. Negara lain yang turun investasinya menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan yang berbentuk penurunan bahkan penghapusan hambatan tarif tidak dapat memberikan insentif bagi investor untuk menanamkan modal. Beberapa penelitian memperlihatkan bahwa terdapat faktor lain, selain tarif, yang lebih dominan dalam mempengaruhi investor untuk melakukan penanaman modal atau Foreign Direct Investment (FDI). Ketersediaan dan kualitas infrastruktur merupakan faktor yang menentukan FDI. Penelitian Cheng dan Kwang (2000); Asiedu (2002); Mai (2002); Carr, Markusen dan Maskus
3 Konsumsi dalam ukuran absolut yang dinilai dalam jumlah atau volume produk pertanian yang dikonsumsi misalnya kg/per kapita bukan dalam bentuk nilai (US$).
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011 - 139
(2004) menunjukkan bahwa infrastruktur mempengaruhi biaya produksi. Selain infrastruktur, kebijakan pemerintah negara tujuan juga mempengaruhi distribusi regional dari aliran masuk FDI
(Cheng et al, 2000; Mai 2002). Kebijakan yang kondusif akan memberikan iklim investasi yang lebih baik dan memberikan insentif bagi investor menanamkam modal.
Tabel 2. Dampak Liberalisasi Perdagangan Sektor Pertanian terhadapMakroekonomi Negara produsen dan importir komoditas pertanian
Sumber: Hasil pengolahan data
Keterangan: Sim 2: Skenario Liberalisasi Perdagangan untuk Komoditas Pertanian sebesar 70 Persen untuk Negara
Maju dan 36 Persen untuk Negara BerkembangSim 3: Skenario Liberalisasi Perdagangan untuk Komoditas Pertanian sebesar 100 Persen untuk Negara
Maju dan Negara Berkembang
140 - Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011
Dampak Liberalisasi Perdagangan Sektor Pertanian terhadap Output dan Perdagangan Sektoral Indonesia
Tabel 4 menyajikan dampak libe-ralisasi perdagangan sektor pertanian terhadap output dan perdagangan sektoral Indonesia dilihat dari output, harga output, ekspor dan impor. Teori ekonomi menjelaskan liberalisasi perdagangan membawa konsekuensi pengurangan restriksi tarif. Secara teoritis, pengurangan restriksi tarif akan
memberikan insentif bagi produsen untuk meningkatkan output dan menurunkan harga agar dapat bersaing dengan produk impor atau dapat meningkatkan output untuk ekspor.
Dampak liberalisasi perdagangan sektor pertanian (dengan lingkup pertanian pada masing-masing sektor di Indonesia) yang dapatdilihat melalui output menunjukkan bahwa sektor gandum, minyak dan lemak4 (dimana CPO tergabung di dalamnya), pertanian
Tabel 3. Dampak Liberalisasi Perdagangan Sektor Pertanian terhadap Makroekonomi Negara produsen dan importir (Lanjutan)
Sumber: Hasil pengolahan data
Keterangan: Sim 2: Skenario Liberalisasi Perdagangan untuk Komoditas Pertanian sebesar 70 Persen
untuk Negara Maju dan 36 Persen untuk Negara BerkembangSim 3: Skenario Liberalisasi Perdagangan untuk Komoditas Pertanian sebesar 100 Persen
untuk Negara Maju dan Negara Berkembang
4 Minyak dan lemak mencakup vegetable oils: crude and refined oils of soya-bean, maize (corn),olive, sesame, ground-nut, olive, sunflower-seed, safflower, cotton-seed, rape, colza and canola, mustard, coconut palm, palm kernel, castor, tung jojoba, babassu and linseed, perhaps partly or wholly hydrogenated,inter-esterified, re-esterified or elaidinised. Termasuk juga dalam kategori ini margarine and similar preparations, animal or vegetable waxes, fats and oils and their fractions, cotton linters, oil-cake and other solid residues resulting from the extraction of vegetable fats or oils; flours and meals of oil seeds or oleaginous fruits, except those of mustard; degras and other residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or vegetable waxes.
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011 - 141
lainnya serta beras merupakan sektor-sektor yang responsif,meskipun dengan besaran (magnitude) respon yang kecil (kurang dari dua persen pada saat skenario pengurangan restriksi sebesar 70 persenuntuk negara maju dan -36 persen untuk negara berkembang) (Tabel 4).
Di sektor pertanian lainnya, sektor-sektor seperti vegetable and fruit; oil seeds; cereal grains nec; sugar cane, sugar beet; meat cattle, sheep, goats, horses; dan sugar adalah sektor yang akan terpukul akibat liberalisasi perdagangan. Sektor-sektor tersebut akan mengalami penurunan output
(Tabel 4). Hal ini menunjukkan bahwa pada realitasnya, produk-produk pertanian Indonesia tersebut belum mempunyai supply response yang memadai dan masih belum siap untuk perdagangan bebas karena belum cukup mampu dilihat dari keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif secara komprehensif sejak dari industri hulu sampai dengan industri hilir. Meskipun demikian, tekanan impor dari negara maju dan berkembang lainnya akan berkontribusi terhadap output, seiring dengan meningkatnya impor sektoral pada sektor-sektor pertanian.
Tabel 4. Dampak Liberalisasi Perdagangan Sektor Pertanian terhadap Sektoral Ekonomi Indonesia
Sumber: Hasil pengolahan data
Keterangan: Sim 2: Skenario Liberalisasi Perdagangan untuk Komoditas Pertanian sebesar 70 Persen
untuk Negara Maju dan 36 Persen untuk Negara BerkembangSim 3: Skenario Liberalisasi Perdagangan untuk Komoditas Pertanian sebesar 100 Persen
untuk Negara Maju dan Negara Berkembang
142 - Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011
Sementara itu, full liberalization memberikan arah efek yang ekuivalen dengan skema liberalisasi perdagangan WTO dengan respon yang lebih elastis. Hal ini ditunjukkan oleh komoditas pertanian yang memberikan respon positif dalam peningkatan output secara konsisten dengan output multiplier antara 250 sampai dengan 350 persen. Sebagai contoh, kenaikan output vegetable oil and fats meningkat dari 1,87 menjadi 6,61 persen (Tabel 4) akibat peningkatan status liberalisasi perdagangan komoditas pertanian dari skenario 2 (liberalisasi perdagangan komoditas pertanian sebesar 70 persen untuk negara maju dan 36 persen untuk negara berkembang) menjadi full liberalization. Respon market price dalam skema liberalisasi perdagangan mengilustrasikan bahwa secara umum tekanan food inflation di level komoditas pertanian Indonesia akan menurun meskipun beberapa komoditas menunjukkan respon penurunan output, sehingga akan berpengaruh terhadap peningkatan purchasing power di level mikro dan rumahtangga.
Dampak Liberalisasi Perdagangan Sektor Pertanian terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral Indonesia
Secara konseptual, ekspansi output sektoral mendorong peningkatan permintaan tenaga kerja. Dengan demikian, rekruitmen terhadap tenaga kerja baik yang terlatih maupun tidak terlatih akan meningkat. Peningkatan permintaan tenaga kerja dalam kondisi suplai tenaga kerja yang tetap akan mendorong peningkatan upah. Namun, dengan kondisi mayoritas output di sektor pertanian yang bernilai negatif, maka penurunan output di sektor-sektor pertanian seperti cereal
grains nec (maize); vegetables, fruit, nuts; sugar cane, sugar beet; cattle,sheep,goats,horses; raw milk; dan meat juga menyebabkan menurunnya permintaan terhadap modal (capital) dan tenaga kerja terampil (skilled) dan tidak terampil (unskilled) di sektor pertanian, bahkan di beberapa sektor non-pertanian seperti oilseed dan leather products, Turunnya nilai output dan ekspor serta meningkatnya impor akan mengurangi penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Hal ini akan meningkatkan pengangguran dan menurunkan tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan menurunkan kesejahteraan sebagian besar masyarakat. Dalam jangka panjang, ketergantungan Indonesia pada sektor pertanian primer seharusnya dikurangi dengan adopsi teknologi pengolahan produk pertanian.
Secara teori apabila terjadi penurunan jumlah barang yang diproduksi (output), maka akan menyebabkan penurunan jumlah tenaga kerja yang diminta, mengingat permintaan tenaga kerja adalah permintaan turunan (derived demand) dari permintaan output. Penurunan permintaan terhadap tenaga kerja tercermin dalam penurunan penyerapan terhadap tenaga kerja terlatih dan tenaga kerja tidak terlatih.
Hasil simulasi menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di hampir keseluruhan sektor pertanian mengalami penurunan kecuali rice dan cereal grain yang memang merupakan sektor yang menampung banyak tenaga kerja di Indonesia (Tabel 5). Namun, liberalisasi perdagangan sektor pertanian tidak mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur (manufacture) seperti food and beverage, mining, oil and gas, manufacturing products, dan
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011 - 143
vegetable oils and fats yang ditunjukkan oleh tetap terjadinya peningkatan penyerapan tenaga kerja pada sektor-sektor tersebut.
Terjadinya peningkatan penye-rapan tenaga kerja di sektor manufaktur diduga karena terjadi realokasi sumber daya input atau faktor produksi dari sektor pertanian ke sektor manufaktur akibat tekanan dari produk pertanian
asal impor yang mengakibatkan produk pertanian domestik tidak mampu bersaing di dalam negeri. Fenomena penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian di satu sisi, dan peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur di sisi lain, akan berimplikasi pada meningkatnya urbanisasi karena sektor manufaktur di Indonesia terkonsentrasi di perkotaan.
Tabel 5. Dampak Skenario Liberalisasi Perdagangan Sektor Pertanian terhadap Kondisi Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia
Sumber: Data Diolah
Keterangan: Sim 2 : Skenario Liberalisasi Perdagangan untuk Komoditas Pertanian sebesar 70
Persen untuk Negara Maju dan 36 Persen untuk Negara BerkembangSim 3 : Skenario Liberalisasi Perdagangan untuk Komoditas Pertanian sebesar 100
Persen untuk Negara Maju dan Negara BerkembangUnSkLab: Unskilled Labor; SkLab: Skilled Labor
144 - Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011
KESIMPULAN
KesimpulanBerdasarkan hasil simulasi dan
analisis dampak liberalisasi perdaga-ngan sektor pertanian terhadap kondisi makro ekonomi di negara produsen dan importir komoditas pertanian serta dampaknya terhadap sektoral ekonomi Indonesia diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:1. Liberalisasi perdagangan sektor
pertanian diprediksi hanya akan berdampak relatif kecil pada peningkatan PDB rill yaitu kurang dari satu persen baik bagi negara maju maupun negara berkembang.
2. Liberalisasi perdagangan sektor pertanian akan memberikan keuntungan bagi negara maju seperti Amerika Serikat, Rusia, dan EU karena akan meningkatkan output atau produksi sektor pertanian mereka, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan menurunkan PDB deflator atau menurunkan tingkat inflasi di wilayah tersebut.
3. Penurunan tarif pada komoditas pertanian akan memberikan kerugian bagi negara berkembang seperti Indonesia, Pakistan, dan Bangladesh karena meningkatnya PDB deflator atau tingkat inflasi yang relatif tinggi.
4. Hasil simulasi menunjukkan bahwa kebijakan liberalisasi perdagangan sektor pertanian berpotensi untuk meningkatkan laju pertumbuhan impor lebih cepat daripada ekspor. Dengan demikian, bagi Indonesia, isu sentral yang harus dicermati mengenai kinerja perdagangan adalah sejauh mana kekuatan penawaran ekspor Indonesia
dapat merespon peluang libe-ralisasi perdagangan. Hasil simulasi memperlihatkan bahwa terdapat keterkaitan positif antara liberalisasi perdagangan sektor pertanian dan investasi di China, Philipina, Bangladesh, dan Brazil, sedangkan di negara lainnya termasuk Indonesia hal tersebut tidak terjadi.
5. Hasil simulasi menunjukkan bahwa sektor gandum, minyak dan lemak (dimana CPO tergabung di dalamnya), pertanian lainnya serta padi dan beras adalah sektor yang sangat responsif terhadap kebijakan liberalisasi perdagangan sektor pertanian.
6. Liberalisasi perdagangan sektor pertanian berdampak negatif ter-hadap output sektor pertanian Indonesia, tetapi menyebabkan peningkatan output di sektor manufaktur. Hal ini diduga karena terjadi realokasi sumber daya input atau faktor produksi dari sektor pertanian ke sektor manufaktur.
Implikasi Kebijakan1. Pemerintah Indonesia harus mem-
proteksi sektor pertanian dari tekanan liberalisasi perdagangan sektor pertanian dalam kerangka WTO agar terhindar dari potensi kerugian akibat liberalisasi ter-sebut.
2. Pemerintah harus menciptakan iklim usaha yang kondusif di sektor pertanian dan menyediakan infrastruktur pendukung yang baik agar Indonesia bisa memperoleh manfaat dari liberalisasi per-dagangan sektor pertanian, berupa peningkatan investasi seperti yang terjadi di beberapa
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011 - 145
negara berkembang seperti China, Philipina, Bangladesh, dan Brazil.
DAFTAR PUSTAKA
Asiedu, E. (2002). On the Determinants of Foreign Direct Investment to Developing Countries : Is Africa Different?. World Development, 30(1), pp. 107-119.
Bauhrer T, Mauro FD. (1995). Computable general equilibrium model as a tools for policy analysis in developing countries: Some basic principles and empirical application. Banca D”talia, Rome.
Carr, D. L., J. R. Markusen, and K. E. Maskus. (2004). Competition for Multinational Investment in Developing Countries: Human Capital, Infrastructure and Market Size, in Challenges to Globalization: Analyzing the Economics - books.google.com.
Cheng Leonard K. and Yum K. Kwan. (2000). What are the determinants of the location of foreign direct investment? The Chinese experience. Journal of International Economics, 51(2) , pp. 379-400.
Badan Pusat Statistik. (2009). Statistik Indonesia 2009. ISSN : 0126-2912. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Jakarta.
Dixix, PT., Josling, and D. Blandford. (2001). The Current WTO Agriculture Negotiations: Option for Progress, Syntesis. International Agricultural Trade Research Consortium Commissioned paper No. 18.
Dixon PB, Parmenter BR, Sutton J, Vincent DP. (1982). ORANI: A Multi-sectoral Model of the Australian Economy. North-Holland, Amsterdam.
Dunn, R.M. (2000). International Economics. Fith Edition. Rout-ledge, New York.
Ellwood, W. (2002). The No-Nonsense Guide to Globalization. New Internationalist Publication: Ox-ford.
FAO. (2010). FAO Statistical Year Book. Rome.
Fukunari, K. (2003). Construction of FTA networks in East Asia. Japan Review of International Affairs. Vol. 17/3: 168-84.
GTAP. (2011). GTAP History. www.gtap.agecon.purdue.edu, diunduh pada tahun 2011
Hardono, G.S., P.S Handewi, dan S.H Suhartini. (2004). Liberalisasi Perdagangan: Sisi Teori, Dampak Empiris dan Perspektif Ketahanan Pangan. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 22(2): 75-88.
Hertel, Thomas W dan Huff Karen M. (2000). Decomposing Welfare Changes in the GTAP Model. GTAP Technical Paper No. 5. Cambridge University Press, New York.
Horridge JM, Parmenter BR, and Pearson KR. (1993). ORANI-F: A General Equilibrium Model of the Australian Economy. Economic and Financial Computing 3 (2) (Summer): 71-140
Horridge M. (2000). ORANI-G: A General Equilibrium Model of the
146 - Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011
Australian Economy. Center of Policy Studies and Impact Project Preliminary Working Paper No. OP-93. Monash University, October. http//www.monash.edu au./policy/elecpapr/op-93.htm.
Horridge M. (2002). ORANIG-RD: A Recursive Dynamic Version of ORANIG. http//www.monash.edu au./policy/oranig.htm.
Joseph, E., Stiglitz, and A. Charlton. (2005). Fair Trade For All, How Trade can Promote Development, Oxford University Press, Oxford, hal. 171-260
Khor, M. (2000). Globalization and The South. Some Critical Issues, Third World Network: Penang Malaysia.
Krueger, A.O. (1999). Are Preferential Trading Arrangements Trade-Liberalizing or Protectionist? Journal of Economic Prespectives, 13(4): 105-124.
Krugman, R.P., Obstfeld, M. 2000. International Economics, Theory and Policy. Fifth Edition. Pearson Adison Wesly, Pearson International Edition. USA.
Mai, Pham Hoang. (2002). Regional economic development and foreign direct investment flows in Vietnam, 1988–1998. Journal of the Asia Pacific Economy 7(2): 182–202.
Michalak, W. dan Gibb, R. (1997). Trading Blocs and Multilateralism in the World Economy. Analysis of the Association of American Geographers. Vol. 87. No. 2. Oxford: Association of American Geographers, 1997. 264-297.
Oktaviani, R dan E. Puspitawati. (2008). Teori, Model, dan Aplikasi GTAP (Global Trade Analysis Project) di Indonesia. Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Oktaviani, R. Widyastutik, dan S. Amaliah. (2010). Manfaat dan Biaya Pendirian Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN China Terhadap Ekonomi Makro dan Sektoral Indonesia. Makalah dipresentasikan pada FGD Kajian Dampak Persaingan Usaha Terkait dengan Pelaksanaan ACFTA. Kerjasama Universitas Airlangga dan KPPU. Surabaya, 23 September 2010.
Oktaviani. R, Iman S, and Anny R. (2003). Bank Restructuring and its Implication on Indonesian Macro Economy and Agriculture Sector. The AARES Conference Paper, Perth Australia.
Oktaviani. R, Sahara, Dwi H, dan Arman D. (2006). Analisis Dampak Perubahan Variabel Ekonomi terhadap Sektor Industri. Departemen Perindustrian RI, Jakarta.
OECD. (2002). Agriculture and Trade Liberalization: Extending the Uruguay Round Agreement. Organization for Economic Cooperation and Development. Paris.
Rahmanto Bambang. (2005). Dampak Liberalisasi Perdagangan Global dan Perubahan Kondisi Ekonomi-Politik Domestic terhadap Dina-mika Perdagangan Luar Negeri
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011 - 147
Kelompok Komoditas Berbasis Pertanian di Indonesia. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Litbang Pertanian, Jakarta.
Salvatore, D. (1997). Ekonomi Internasional. Haris Munandar [Penerjemah]. Erlangga, Jakarta.
Sawit, M.H. (2001). WTO dan Nasib Negara Miskin. Medium 65, 12 – 26, April.
Sawit, M.H. (2003). The Development of the WTO agreement of Agriculture: Harbonson Proposal and Indonesian need. Paper presented in Road to Cancun: Indonesian preparation to the next WTO Agreement. Jakarta.
Simatupang, P. (2004). Justifikasi dan Metode Penetapan Komoditas Strategis. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
Suryana, A. (2004). Arah, Strategi dan Program Pembangunan Pertanian 2005–2009. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor, 4 Agustus 2004.
Yeah KL, Yanogida JF, Yamauchi H. (1994). Evaluation Of External Market Effects And Government Intervention In Malaysia’s Agicultural Sector: A computable general equilibrium framework. Journal of Agricultural Economic Research 11 (2): 237-256.
148 - Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011
PENDAHULUANSusastro (2004) menemukan
bahwa liberalisasi merupakan salah satu langkah efektif dalam meningkatkan daya saing nasional di pasar global. Kondisi ini tercipta karena liberalisasi mendorong kinerja perekonomian menjadi lebih efisien melalui aplikasi tehnologi baru sebagai implementasi liberalisasi di sektor perdagangan dan investasi. Liberalisasi melalui rangkaian kerjasama bilateral, regional maupun bilateral merupakan kondisi yang tidak dapat dihindari lagi.
Perundingan multilateral terse-but saat ini dikenal dengan Doha
Development Agenda (DDA), yang telah berlangsung sekitar 8 tahun. Namun sayangnya, sampai saat ini masih belum satupun isu perundingan dapat diselesaikan. Jika negosiasi tersebut berhasil dirampungkan, akan terjadi liberalisasi produk barang dan jasa yang akan dilaksanakan serempak di seluruh dunia. Adapun tujuan dari pelaksanaan liberalisasi tersebut adalah penurunan proteksi domestik yang akan meningkatkan impor produk pertanian di dunia, termasuk Indonesia.
Banyak pihak yang khawatir liberalisasi tersebut akan memberikan dampak buruk bagi petani nasional,
DAMPAK LIBERALISASI WTO TERhADAP KETAHANAN PANGAN BERAS DAN GULA
Oleh :Adrian D. Lubis1 Reni K. Arianti2
Naskah diterima : 5 Oktober 2011Disetujui diterbitkan : 10 Desember 2011
AbstractThis paper goals are to study impact of trade liberalization and Indonesia capability to maintain national food security for rice and sugar. This study that uses multiregression analysis with dummy variabels and GTAP found that import of rice and sugar increase due are to lack of capability to fulfill national consumption. Therefore, Indonesia must increase its rice and sugar productivity to fulfill national food security in liberalization regime.
Keywords: Revealed Comparative Advantage Bilateral, Liberalisasi
JEL Classification: F12, F13, F15
1 Peneliti pada Pusat Kebijakan Kerjasama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan, Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta. E-mail : [email protected]
2 Peneliti pada Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta. E-mail : [email protected]
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011 - 149
sebagaimana pernyataan Hadi (2008), Rachman, et.al. (2008) dan Hutabarat (2006). Oleh karena itu, untuk memperoleh prediksi atas dampak liberalisasi WTO, terdapat beberapa hal yang perlu untuk dianalisis yaitu 1) Faktor apakah yang mempengaruhi impor produk pertanian, 2) Bagaimana dampak keikutsertaan Indonesia dalam liberalisasi WTO terhadap kinerja sektor pertanian dalam memenuhi ketahanan pangan khususnya ketersediaan pangan, dan 3) Bagaimanakah Indonesia menyikapi dampak liberalisasi tersebut untuk dapat meningkatkan kinerja sektor pertanian dalam memenuhi ketahanan pangan?
TINjAUAN PUSTAKAMenurut Apriyantono (2006), jika
ditelusuri ke belakang, pada saat kita berbicara soal liberalisasi Perdagangan, sebenarnya upaya global itu telah dimulai sejak tahun 1947 dengan dirancangnya General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Negosiasi tentang perdagangan ini memakan waktu cukup lama, sampai delapan putaran, yang berakhir tahun 1994. Putaran terakhir, Putaran Uruguay, yang berlangsung dalam periode 1986-1994, ditutup di Marakesh, Moroko pada awal 1994, kemudian dibentuk badan perdagangan dunia yang kemudian dikenal nama World Trade Organization (WTO).
Dalam delapan putaran itu, dan juga Putaran Doha sekarang ini, pembahasan tentang liberalisasi perdagangan sangat terfokus pada pengurangan tingkat tariff, dan semuanya terkait dengan akses pasar (market access). Artinya, perdagangan internasional telah terperangkap pada sisi permintaan (demand side)
dan mengabaikan sisi penawaran (supply side). Padahal, memecahkan hambatan dari sisi penawaran sangat erat kaitannya dengan kemampuan negara berkembang untuk dapat meraih keuntungan dari terbukanya akses pasar (Apriyantono, 2006).
Pentingnya sisi penawaran dalam perdagangan internasional telah diungkapkan oleh Rubens Ricupero, mantan Sekjen UNCTAD, pada suatu pertemuan Trade and Development Board UNTAD, di Jenewa 15 Oktober 2003 lalu. Ia mengatakan antara lain: ”Akar masalah dari keengganan banyak negara berkembang untuk terlibat dalam liberalisasi perdagangan, karena mereka tidak cukup kompetitif, disamping mereka sendiri mengandalkan pada dua-tiga jenis komoditas saja untuk ekspor” (Apriyantono, 2006).
Apriyantono (2006) menyatakan banyak kendala yang dihadapi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam memperkuat dan memanfaatkan sisi penawaran, seperti masalah kualitas SDM, enerji, infrastruktur yang meliputi sarana prasarana transportasi (termasuk pelabuhan), teknologi komunikasi dan informasi. Aspek lainnya yang tidak kalah penting adalah kestabilan politik dan ekonomi. Apabila ke dua sisi itu tercapai, maka hal tersebut akan memperkuat kapasitas produksi, mengurangi ongkos produksi, serta meningkatkan daya saing. Selanjutnya, sisi penawaran penting lainnya adalah membuka akses sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) terhadap pendanaan (finance), meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan buat mereka, perbaikan manajemen dan keahlian. Hal tersebut diharapkan agar mereka terkait dengan global supply chain
150 - Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011
(rantai pasokan global), bukan seperti sekarang ini.
Namun, Bursfier (2001) menyatakan bahwa hambatan per-dagangan untuk produk pertanian dan subsidi meningkatkan biaya bagi negara tersebut dan mitra dagangnya. Hambatan perdagangan dalam bentuk tarif akan mengurangi permintaan produk di negara mitra, namun disisi lain subsidi menyebabkan kelebihan produksi domestik. Kedua kebijakan tersebut jika terjadi bersamaan akan menyebabkan turunnya harga produk pertanian. Bursfier menyatakan bahwa eliminasi distorsi perdagangan akan meningkatkan kesejahteraan penduduk dunia sebesar US $ 56 miliar. Adapun instrumen yang umum digunakan dalam hambatan perdagangan adalah tarif. Oleh karena itu, di tahun 2010, negara anggota WTO sepakat melakukan
reformasi perdagangan melalui serangkaian kebijakan penurunan tarif dan subsidi.
Gambar 1 menunjukkan per-ubahan hambatan tarif semenjak negosiasi Uruguay Round sampai negosiasi Doha Development Agenda saat ini. Hasil negosiasi Uruguay Round adalah kesepakatan penurunan tarif menjadi maksimal 100 persen. Selanjutnya, tarif tersebut dalam negosiasi Doha Development Agenda diusahakan untuk turun lagi menjadi maksimal 50 persen. Tarif maksimal 50 persen adalah tarif tertinggi yang dapat diaplikasikan atau dikenal dengan bound rate. Jika terdapat petani dari produk pertanian tertentu mengalami kerugian akibat liberalisasi tersebut, masih dapat diselamatkan melalui mekanisme spesial safeguard mechanism (SSM)
Gambar 1. Skema Liberalisasi Multilateral
Sumber: WTO (2008)
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011 - 151
Saat ini terdapat 2 hal teknis yang sangat penting dalam negoisasi WTO selanjutnya. Pertama, yakni besaran remedy yang dapat diterapkan berikut dengan besaran rentang lonjakan. Adapun remedy merupakan peningkatan pajak impor untuk mengembalikan harga ke tingkat semula. Kedua, cara dalam menentukan besaran trigger. Trigger merupakan batas tertinggi peningkatan impor sebelum dilakukan remedy. Pendekatan yang selama ini diusulkan dan cukup banyak diterima adalah dengan menggunakan Moving Average (MA), khususnya MA 3. Beberapa pendekatan lain yang sempat diwacanakan adalah penggunaan MA 5, fixed reference prices dan olympic average price (dengan menghilangkan nilai yang terbesar dan terkecil, setelah itu baru dihitung rata-ratanya). Kedua poin ini yang terus menerus dinegoisasikan selain dari tuntutan negara berkembang agar negara maju mau menurunkan dan bahkan menghilangkan subsidi ekspor yang mereka berikan.
Jika perhitungan trigger didasarkan pada harga, maka kejatuhan harga didefinisikan sebagai perubahan harga relatif terhadap rata-rata harga impor tiga tahun sebelumnya. SSM akan berlaku jika terjadi kejatuhan harga c.i.f sebesar 85 persen dari rata-rata harga impor tiga tahun sebelumnya. Besaran remedy yang diterapkan adalah sebesar 85 persen dari perbedaan harga impor dan harga trigger.
Perlakuan Spesial dan Berbeda Bagi Negara Berkembang Dalam Negosiasi WTO
Negara berkembang menerima perlakuan yang berbeda mengenai perhitungan safeguard yang disebut special and differential treatment, dalam
hal pengecualian de minimis volume impor. Sebagai pengguna safeguard, negara berkembang menerima perlakuan berbeda untuk menghargai perhitungan mereka masing-masing, misalnya dengan mengecualikan durasi perpanjangan.
Pada konsep pengecualian impor de minimis, langkah safeguard tidak dapat diterapkan untuk menekan volume ekspor dari negara berkembang; yaitu, ketika impor dari suatu negara berkembang kurang dari 3% dari total impor pada produk yang diteliti. Dalam klausul ini, negara berkembang yang berada dibawah ambang tersebut secara individu dan secara kolektif lebih dari 9 persen dari impor tersebut, impor tersebut dapat dikeluarkan dari perhitungan.
Dalam pemberlakuan konsep safeguard, negara-negara berkembang dapat memperpanjang kebijakan safeguard selama dua tahun ekstra dari durasi normal yang di ijinkan. Aturan-aturan untuk melaksanakan safeguard nya pun diberlakukan secara fleksibel. Misalnya periode minimum tidak diterapkan, dalam banyak kasus dalam satu setengah durasi dari perhitungan normal, jadi paling lama pemberlakukannya setidaknya dua tahun.
Namun perlakuan khusus ini menjadi salah satu penyebab kebuntuan pembicaraan di 2008 yang dipicu oleh ketidaksepakatan terkait dengan parameter trade remedies dalam mekanisme special safeguard pertanian untuk negara berkembang. Tidak ada kesepakatan dasar mengenai kondisi seperti apa yang menjadi prasyarat utama penerapan SSM. Secara spesifik, isu-isu penting yang menjadi perhatian dan menyebabkan kebuntuan
152 - Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011
pembicaraan bukan hanya seberapa besar pengaruh impor terhadap kenaikan atau penurunan harga dalam negeri sebelum trade remedies diterapkan, tetapi jika dilakukan, dengan parameter dari seberapa besar kemampuan negara berkembang menaikan tarifnya dalam kerangka tarif yang berlaku (pra-Doha), dan seberapa banyak produk yang dapat dilibatkan.
SUMBER DATA DAN METODOLOGI Kajian ini berusaha untuk
menjawab faktor yang mempengaruhi impor produk pertanian, dampak liberalisasi dan kemampuan mem-pertahankan ketahanan pangan dengan menggunakan: (1) data perdagangan yang diterbitkan oleh Statistik Indonesia
maupun devisi statistik dari Food and Agrigulture Organization (FAO) untuk menganalisa lonjakan impor produk pertanian di Indonesia, (2) data perubahan produksi dan konsumsi produk pangan yaitu beras dan gula dari devisi statistik FAO, dan (3) data primer yang bertujuan mengontrol hasil prediksi dengan kondisi riil di lapangan.
Metodologi yang digunakan adalah persamaan regresi berganda dengan variabel dummy yang diilhami oleh model gravitasi yang dibangun McCallum (1995). Berdasarkan model tersebut dibangun persamaan 1 untuk memprediksi dampak perubahan kinerja perekonomian khususnya GDP, dan liberalisasi terhadap impor produk beras atau gula nasional sebagai berikut :
lnMij = a1 + a2 ln yi + a3 ln pi + a4 ln ci + a5 ln dij + ... + εij
dimana : Mij adalah impor Indonesia untuk komoditas beras atau gula dari dunia, yi adalah nilai GDP Indonesia, p adalah produksi komoditas beras atau gula nasional, ci adalah konsumsi komoditas beras atau gula nasional, dan d merupakan dummy liberalisasi yaitu AFTA, KAFTA, IJEPA.
Selanjutnya akan dilakukan simulasi untuk memprediksi dampak liberalisasi dengan menggunakan model keseimbangan umum Global Trade Analysist Project (GTAP) versi 62. Adapun simulasi yang dilakukan terdiri dari simulasi A, yaitu dampak liberalisasi yang sudah terjadi antara Indonesia dengan sesama negara ASEAN yang dikenal dengan ASEAN
Free Trade Agreement (AFTA), Korea ASEAN Free Trade Agreement (KAFTA) dan Indonesia Jepang Economic Partnership Agreement (IJEPA). Selanjutnya dilakukan simulasi B yaitu simulasi A ditambah dengan prediksi dampak liberalisasi sesuai perjanjian WTO. Adapun simulasi yang dilakukan dalam kajian ini terdiri dari dua bagian yang dapat dilihat selengkapnya dalam Tabel 1.
Simulasi liberalisasi bertujuan untuk menganalisis dampak komitmen Indonesia dalam liberalisasi dengan mitra regional dan bilateral dibandingkan liberalisasi dunia (DDA-WTO). Analisis ini bertujuan untuk menganalisis apakah liberalisasi antara
2 Model ini dikembangkan oleh Thomas W. Hertel, Profesor dari Central for Global Trade Analysis, Department of Agricultural Economic, Purdue University
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011 - 153
Indonesia dengan dunia berdampak negatif bagi peningkatan produksi, dan kesejahteraan, jika disaat bersamaan
Indonesia melakukan liberalisasi dengan mitra dagang utama terutama ASEAN, Korea dan Jepang.
Tabel 1. Simulasi Liberalisasi
HaSiL dan PembaHaSanPerubahan Luas areal Padi dan Tebu
Salah satu indikasi penting perubahan produksi beras dan gula nasional bisa diketahui melalui perubahan luas areal padi dan tebu. Perubahan luas areal kedua produk tersebut dapat dilihat selengkapnya dalam Gambar 2. Luas areal padi
selama tahun 1990 sampai dengan tahun 2009 menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Luas areal padi di tahun 1990 mencapai 10,5 juta hektare HA dan meningkat di tahun 2009 mencapai 12,8 juta HA. Peningkatan ini relatif signifikan selama periode 1990-2009, meskipun terjadi fluktuasi dalam beberapa tahun.
3 Paper dibuat di awal 2010, sebelum pemberlakuan liberalisasi dengan China dan Australia-Selandia Baru
154 - Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011
Luas areal tebu relatif lebih berfluktuasi dibandingkan luas areal padi. Luas areal tebu mengalami peningkatan dari 345 ribu HA di tahun 1990 menjadi 420 ribu HA di tahun 2009. Namun, di tahun 1996 sampai tahun 2003 luas areal tebu mengalami penurunan drastis dari 430 ribu HA menjadi 335 ribu HA.
Produksi Beras4 dan Gula Produksi beras selama tahun
1990 sampai 2009 menunjukkan pertumbuhan signifikan. Produksi beras di tahun 1990 mencapai 45,17 juta ton dan meningkat menjadi 64,39 juta ton di tahun 2009. Pertumbuhan ini
menunjukkan produksi beras bertambah sebesar 1,17 persen per tahun selama periode tersebut.
Sedangkan produksi gula se-lama periode tersebut ternyata sangat fluktuatif. Produksi gula di tahun 1990 mencapai 27,97 juta ton, dan meningkat menjadi 33 juta di tahun 1993. Namun, setelah tahun tersebut, produksi gula turun mencapai titik terendah, mencapai 23,5 juta di tahun 1999. Selanjutnya produksi gula mengalami peningkatan mencapai titik tertinggi di taun 2005, namun kembali menurun dan akhirnya di tahun 2009 produksi gula nasional mencapai 26,5 juta ton.
Gambar 2. Luas Areal Padi dan Tebu
Sumber : www.fao.org
4 Selanjutnya untuk produksi beras merupakan produksi beras setara gabah
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011 - 155
Jika dibandingkan dengan produksi produk pertanian dan peternakan lainnya, Indonesia berhasil mempertahankan produksi beras jauh diatas produk lain selama 1990-2009. Namun untuk gula tebu, mengalami penurunan dari posisi delapan terbesar di tahun 1990 menjadi posisi
kelimabelas di tahun 2009. Adapun produk yang mengalami peningkatan drastis adalah kelapa sawit dan karet. Hal ini menunjukkan salah satu permasalahan dalam mempertahankan produksi pangan adalah kompetisi lahan dengan produk komersil.
Gambar 3. Produksi Padi dan Tebu
Sumber : www.fao.org
Tabel 2. Perbandingan Produksi 20 Produk Pertanian dan Peternakan di Tahun 1990-2009
156 - Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011
Konsumsi Beras dan Gula TebuKonsumsi beras dan gula
menunjukkan pola yang sama dengan produksi beras dan gula tebu dalam Gambar 4. Konsumsi beras di tahun 1990 mencapai 45,18 juta ton dan meningkat sehingga mencapai 64,51 juta ton di tahun 2009, sedangkan produksi di tahun 1990 sebesar
45,18 juta ton dan meningkat menjadi 64,39 juta ton di tahun 2009. Kondisi ini memperlihatkan konsumsi beras selama 1999-2009 masih lebih besar dibandingkan kemampuan produksi nasional. Jika kondisi ini terus berlanjut, impor beras masih dibutuhkan untuk menjaga stabilitas harga beras.
Sumber : www.fao.org
Gambar 4. Konsumsi Beras dan Gula Tebu Nasional
Sumber : www.fao.org
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011 - 157
Adapun konsumsi gula tebu di tahun 1990 mencapai 28,23 juta ton, namun di tahun 2009 turun 27,78 juta ton di tahun 2009. Volume konsumsi dengan produksi gula tebu hampir berbeda satu juta ton selama 1990-2009. Hal ini menunjukkan Indonesia masih tergantung pada impor gula tebu untuk memenuhi konsumsi nasional.
Sayangnya, angka konsumsi beras dan gula tebu merupakan angka perhitungan yang diperoleh dari penjulahan produksi dengan impor dikurangi ekpor. Hal ini disebabkan tidak tersedianya data konsumsi gula nasional. Jika data volume riil konsumsi
gula tersedia, kemungkinan nilai jauh lebih besar.
Korelasi Impor dan Produksi BerasSelama tahun 1990 sampai
dengan 2005 terdapat pola yang menunjukkan impor beras mengalami peningkatan di saat produksi beras menurun. Pola tersebut terlihat antara lain ditahun 1993, 1994 dan 1997. Sebelum tahun 1998, terlihat peningkatan impor juga terjadi saat produksi meningkat. Kondisi ini diperkirakan akibat pada periode tersebut Indonesia sering dilanda bencana sehingga diperlukan banyak cadangan beras.
Gambar 5. Perubahan Produksi dan Impor Beras
Sumber : www.fao.org
Kondisi di atas menyebabkan tingginya korelasi antara produksi dengan nilai impor beras. Hasil perhitungan korelasi Pearson menunjukkan bahwa korelasi antara produksi beras dengan impor selama tahun 1990-2009 mencapai 0,608. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan produksi sebesar 10 persen ternyata diikuti dengan peningkatan impor sebesar 6,8 persen.
Hasil perhitungan dengan metode Pearson juga menunjukkan
bahwa peningkatan impor juga ber-hubungan erat dengan nilai konsumsi. Nilai korelasi keduanya mencapai 0,75 persen, yang berarti peningkatan konsumsi sebesar 10 persen diikuti dengan peningkatan impor sebesar 7,5 persen.
Selain itu, berdasarkan hasil analisis regresi, ditemukan bahwa impor beras berhubungan erat dengan peningkatan volume konsumsi dan pelaksanaan liberalisasi ASEN Korea (DKAFTA). Namun
158 - Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011
volume impor beras berhubungan terbalik dengan peningkatan volume produksi, pelaksanaan liberalisasi ASEAN (DAFTA) dan Indonesia
Jepang (DIJEPA). Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh persamaan yang mempengaruhi impor beras Indonesia sebagai berikut :
Impor Beras = - 88.2 + 49.1 Volume Konsumsi - 43.4 Volume Produksi - 0.33 DAFTA - 1.15 DKAFTA - 0.30 DIJEPA
Berdasarkan persamaan di atas, terlihat bahwa Indonesia mengimpor beras disebabkan kebutuhan nasional dibandingkan pelaksanaan liberalisasi. Kondisi ini menunjukkan jika Indonesia memilih untuk melakukan proteksi untuk produk ini, diharapkan proteksi tersebut juga mempertimbangkan kebutuhan konsumsi nasional agar tidak merugikan kesejahteraan rakyat.
Korelasi Impor dan Konsumsi GulaPerubahan produksi dan
impor gula menunjukkan pola yang berlawanan selama tahun 1990-1999. Namun, pola ini mengalami perubahan semenjak tahun 2000 sampai saat ini. Setelah tahun 2000, terlihat bahwa pola impor gula mengalami perubahan tajam disaat perubahan produksi tidak signifikan. Kondisi tersebut terlihat sangat jelas selama tahun 2003 sampai tahun 2006.
Hasil uji korelasi Pearson menunjukkan bahwa hubungan antara produksi gula dengan impor gula adalah -0,57. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan produksi gula sebesar 10 persen diikuti dengan penurunan impor sebesar 5,7 persen.
Namun, hasil uji regressi dengan variabel berganda dan variabel dummy justru menunjukkan hal berbeda. Hasil uji regresi menunjukkan impor gula berhubungan negatif dengan volume konsumsi dan pelaksanaan liberalisasi Indonesia Jepang (DIJEPA). Namun impor tersebut berhubungan positif
Gambar 6. Perubahan Produksi dan Impor Gula
Sumber : www.fao.org
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011 - 159
dengan peningkatan volume produksi, pelaksanaan liberalisasi sesama negara ASEAN (DAFTA) dan liberalisasi dengan
Impor Gula = 4.8 - 81.6 Volume Konsumsi + 82.0 Volume Produksi + 0.073 DAFTA + 0.625 DKAFTA - 0.747 DIJEPA
Korea (DKAFTA). Adapun persamaan impor gula dapat dirumuskan sebagai berikut :
Hasil regresi di atas menunjukkan pola yang tidak konsisten jika dibandingkan dengan pola impor beras. Adanya hubungan negatif antara konsumsi dengan impor memperlihatkan prediksi penurunan konsumsi menyebabkan importir gula membatasi impor gula. Namun, disaat bersamaan ternyata peningkatan volume produksi juga diikuti dengan peningkatan impor gula. Kondisi ini mungkin disebabkan karena tidak ada badan seperi BULOG yang saat ini menjadi penjaga stabilitas ketersediaan gula nasional, sehingga memungkinkan terjadi aktifitas pengambilan keuntungan dalam perdagangan gula nasional.
Simulasi Liberalisasi WTO Dan Dampaknya Terhadap Produksi, Konsumsi Dan Impor Produk Beras Dan Gula Nasional
Telah banyak penelitian yang dilakukan untuk memprediksi dampak liberalisasi terhadap kinerja nasional dalam menjamin ketahanan pangan. Namun, saat ini Indonesia telah melakukan liberalisasi perdagangan dengan mitra dagang utama seperti terlihat dalam Tabel 3.
Tabel 3 memperlihatkan bahwa tarif yang diberlakukan Indonesia untuk mitra dari negara ASEAN telah nol semenjak tahun 2010. Adapun tarif yang diberlakukan Indonesia untuk negara China telah mengalami penurunan signifikan semenjak tahun 2009, dan akan menjadi nol di tahun 2012 kecuali untuk beras dan gula tidak mengalami perubahan. Selanjutnya, Indonesia juga telah menurunkan tarif untuk Korea dan Jepang semenjak tahun 2007 dan dijadwalkan akan menjadi nol di tahun 2013.
Tabel 3. Perubahan Tarif Rata-Rata Indonesia dan Beberapa Negara Mitra (Persen)
Sumber : Tim Tarif, diolah
160 - Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011
Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa tarif internasional (most favorite nation : MFN) sebesar 7,49-7,5 saat ini hanya berlaku negara yang belum memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Amerika Selatan, negara teluk dan sekitarnya. Adapun bagi mitra lain seperti halnya India dan Australia, akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia. Menyadari kondisi di atas, maka jelas bahwa liberalisasi WTO yang diaplikasikan dengan melakukan penurunan tarif MFN diprediksikan tidak memberikan dampak sebesar liberalisasi lainnya.
Dampak Liberalisasi Terhadap Surplus Perdagangan dan Kese-jahteraan
Hasil analisis menunjukkan bahwa liberalisasi yang saat ini telah berlangsung menyebabkan penurunan surplus perdagangan untuk produk beras, gula dan jasa nasional, namun meningkatkan surplus produk pertanian lain dan manufaktur. Kondisi ini disebabkan Indonesia tidak memiliki daya saing untuk beras dan gula serta sektor jasa dibandingkan negara lain, sehingga memilih mengimpor karena harganya lebih murah. Adapun hasil analisis selengkapnya tercantum dalam Tabel 4.
Berdasarkan simulasi B, jika Indonesia ikut meratifikasi liberalisasi WTO setelah melaksanakan perjanjian liberalisasi dengan ASEAN, Korea dan Jepang, hasil simulasi menunjukkan bahwa surplus perdagangan beras dan gula serta produk jasa semakin turun dibandingkan kondisi dalam simulasi A. Penurunan surplus tersebut disebabkan Indonesia semakin banyak mengimpor
Tabel 4. Dampak Liberalisasi Terhadap Surplus Perdagangan (US $ Juta)
Sumber : GTAP v.6, diolah
produk beras dan gula, namun, dikompensasi dengan peningkatan ekspor produk pertanian lain dan manufaktur.
Jika dibandingkan dengan negara mitra, ternyata kinerja perdagangan Indonesia untuk produk beras dan gula jauh lebih rendah dibandingkan ASEAN lain, dimana eksportir utama untuk produk beras dan gula tersebut
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011 - 161
adalah Vietnam dan Thailand. Kondisi yang sama terjadi dalam simulasi A dan simulasi B, dimana ini disebabkan daya
saing dan produktifitas Indonesia lebih rendah dibandingkan mereka.
Tabel 5. Dampak Liberalisasi Terhadap Kesejahteraan (US $ Juta)
Sumber : GTAP v.6, diolah
Hasil simulasi memperlihatkan bahwa kesejahteraan masyarakat meningkat semenjak liberalisasi. Kondisi ini disebabkan peningkatan konsumsi masyarakat karena memperoleh akses untuk produk yang lebih murah. Hasil simulasi memprediksikan, jika Indonesia mengikuti liberalisasi WTO, kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat karena akses barang murah semakin banyak tersedia.
Dampak Liberalisasi Terhadap Produksi Nasional
Hasil simulasi menunjukkan bahwa produksi nasional hampir tidak mengalami perubahan sebagai akibat pelaksanaan liberalisasi dalam simulasi A maupun B. Namun terlihat bahwa pelaksanaan liberalisasi Indonesia dengan ASEAN, Korea dan Jepang hampir tidak meneningkatkan produksi nasional. Kondisi yang hampir sama juga terjadi saat Indonesia ikut serta dalam liberalisasi WTO. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan akses pasar tidak menciptakan peningkatan
permintaan impor yang signifikan untuk mendorong peningkatan produksi. Hal ini disebabkan proteksi dalam bentuk tarif sudah semakin rendah dan tidak signifikan mempengaruhi permintaan impor di dunia.
Dampak Liberalisasi Terhadap Perubahan Impor Indonesia
Hasil simulasi A menunjukkan bahwa peningkatan impor produk sensitif Indonesia terutama beras dan gula lebih banyak berasal dari sesama negara ASEAN, antara lain Thailand dan Vietnam. Namun diproyeksikan, jika Indonesia ikut serta dalam liberalisasi WTO, akan menurunkan total impor nasional untuk beras dan gula. Selain itu, data dalam Tabel 7 memperlihatkan liberalisasi WTO akan mengurangi impor Indonesia dari ASEAN, namun sebaliknya meningkatkan impor beras dan gula dari kawasan lain. Hasil ini menunjukkan bahwa liberalisasi WTO akan mengurangi ketergantungan nasional atas pasokan beras dan gula impor dari ASEAN.
162 - Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011
Sumber : GTAP v.6, diolah
Tabel 6. Dampak Liberalisasi Terhadap Produksi Nasional (Persen)
Tabel 7. Dampak Liberalisasi Terhadap Impor Indonesia (US $ Juta)
Sumber : GTAP v.6, diolah
Hasil simulasi juga menunjuk-kan liberalisasi WTO justru menurunkan nilai impor Indonesia disetiap sektor. Temuan ini sesuai dengan temuan dari Burfisher (2001). Dalam kajiannya
Burfisher menyatakan bahwa libe-ralisasi multilateral akan mendorong alokasi sumber daya dan menciptakan perdagangan yang lebih adil dan sesuai dengan daya saing setiap negara.
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011 - 163
KESIMPULAN Kesimpulan yang dapat diambil
dari kajian ini adalah pertama, impor beras dan gula cenderung meningkat semenjak tahun 2007 sampai saat ini, lebih disebabkan penurunan ketahanan pangan nasional akibat peningkatan konsumsi lebih besar dari produksi. Kedua, liberalisasi WTO mengurangi ketergantungan impor nasional ter-hadap beras dan gula asal ASEAN, dan membantu menyehatkan neraca perdagangan.
Oleh karena itu, ketakutan banyak pihak atas dampak buruk liberalisasi WTO terhadap ketahanan pangan ternyata tidak beralasan. Keikutsertaan Indonesia dalam liberalisasi pertanian justru meningkatkan ketahanan pangan khususnya ketersediaan pangan nasional. Namun, menyadari peran produk beras dan gula bagi kepentingan nasional, direkomendasikan keikut-sertaan Indonesia dalam liberalisasi tersebut harus diikuti upaya mening-katkan produktifitas beras dan gula nasional.
DAFTAR PUSTAKAApriyantono, A. (2006). Liberalisasi
Perdagangan Dan Pembangunan Pertanian. Bahan Kuliah Umum Menteri Pertanian Pada Program Magister Ilmu Hubungan Inter-nasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta.
Anderson, J. A. (1996). Effective Protection Redux. NBER Working Paper Series No. 5854.
Aswicahyono, H. (2004). Competitive-ness and Efficiency of the Forest Product Industry in Indonesia. Policy Paper Series on The Impact of the Economic Crisis on
the Forestry Sector in Indonesia. A CSIS-John D and Catherine T. Mac Arthur Foundation Project, February.
Burfisher, M. E. (2001). The Road Ahead: Agricultural Policy Reform in the WTO--Summary Report. Agricultural Economic Report No. (aer797) 32 pp, January.
Departemen Perdagangan, (2009). Menuju Daya Saing Bangsa Dan Kemakmuran Rakyat. Pem-bangunan Perdagangan 2005-2009. Jakarta.
Hadi, S. (2008). Perdagangan Bebas dan Pembangunan, Kompas. diakses dari http://cetak.kompas.com pada Juli 2011.
Hertel dan Tsigas. (1997). Structure of GTAP, Global Trade Analysis, Modeling and Applications. Cambridge University Press, New York.
McCallum, J. (1995). National Borders Matter: Canada-US Regional Trade Matters. American Econo-mic Review. June, 85(3), pp.615-623.
Rachman, H.P.S., S.H. Suhartini, dan G. S. Hardono.(2008). Dampak Liberalisasi Perdagangan Ter-hadap Kinerja Ketahanan Pangan, Pengembangan Inovasi Pertanian 1(1), Hal.: 47-55
Susastro, H. (2004). Kebijakan Persai-ngan, Daya Saing, Liberalisasi, Globalisasi, Regionalisasi dan Semua Itu. Economic Working Papers Series. CSIS, Jakarta.
Tambunan, T. (2008). Ketahanan Pangan Di Indonesia Inti Permasalahan Dan Alternatif Solusinya. Makalah dipersiapkan untuk Kongres ISEI, Mataram.
164 - Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011
INTRODUcTIONIndonesia and China trade has
more relationship especially since after the implementation of ASEAN- China Free Trade Agreement (ACFTA) in July 2005. The global financial crisis and China high economic growth are the other phenomenon contributed to the closer trade relationship. The shrinking demand from USA, European countries and Japan as the impact of global economic crisis has drive Indonesian product to China’s market. The Indonesian Ministry of Trade has
1 Peneliti Pertama pada Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta. E-mail: [email protected]
released the share of Indonesian non oil and gas export to China which increased from 6.0% in 2005 to 9.1% in 2009. On the other side, the share of imported non oil and gas China increased from 11.3% in 2005 to 17.3% in 2009 (Ministry of Trade, Republic of Indonesia, 2011).
This study attempts to analyze the competitiveness of Indonesia’s products in trade relationship with China. The empirical statistic analysis called International Competitiveness coefficient (ICC) is used to examine the
The ComPeTiTiVeNeSS of iNDoNeSiAN PRoDuCT iN TRADe ReLATioNShiP wiTh ChiNA
Oleh : Umar Fakhrudin1
Naskah diterima : 21 Juli 2011Disetujui diterbitkan : 2 Desember 2011
AbstractHubungan perdagangan Indonesia dan China semakin erat setelah
implementasi ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) dimulai pada bulan Juli 2005. Krisis keuangan global dan pertumbuhan ekonomi China yang cukup tinggi merupakan fenomena lain yang berkontribusi pada semakin eratnya hubungan kedua negara. Tulisan ini mencoba menganalisis daya saing produk Indonesia dalam hubungan perdagangan dengan China dengan menggunakan analisis statistik Koefisien Daya Saing Internasional (ICC). Hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan perdagangan antara Indonesia dan China memberikan daya saing lebih untuk China. Walaupun demikian, ada beberapa produk Indonesia yang memiliki daya saing tinggi dan mengalami peningkatan selama periode tahun 2005 -2009. Produk –produk tersebut antara lain; daging, kakao, karet dan produk karet, bahan anyaman (termasuk rotan dan bambu), tekstil dan garmen, alas kaki, serta bahan tambang seperti besi dan batubara.
Keywords: Trade, China, Competitiveness, International Competitiveness Coefficient
JEL Classification : F10,F14, F17
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011 - 165
competitiveness of Indonesia’s products in trade relation with China. Please give more details of the order of the article.
International Competitiveness Coefficient (ICC)
International Competitiveness Coefficient (ICC), or sometimes known as Trade Specialization Index (TSI), is used to analyze the position of development of a product and show its competitiveness. ICC can describe whether for any type of product, a country tends to be an exporters or importers (Tambunan & Suparyati, 2009). In mathematical term, ICC can be formu-lated as follows:
X and M are export and import respectively. i and a are goods of type i and country a respectively. Implicitly, ICC index considers as the demand side and supply side. Exports of goods will occur when there is an excess of goods in domestic market. The value of this index has range between -1 to +1. The positive value (between 0 and 1 indicates that respective commodity has a strong competitiveness or a respective country tend to be an exporter of the commodity (domestic supply is greater than domestic demand). Conversely,
the negative value below 0 to -1 means low competitiveness of the respective products and the country tends to be an importer. If the index increases, it means that the competitiveness of the product increases, and vice versa.
The data used for analysis are collected from UNCOMTRADE using the World Integrated Trade Solution (WITS). Harmonization System (HS) Revision 1996 code 2 digit is used in the analysis to simplify the calculation. There are 96 aggregation items, then it is called as product. Product with HS 2 digit are classified into three main sectors: agriculture; manufacture and oil; mining, mineral and metal. The agriculture products consist of HS 01 – HS 24 and HS 40 – 44; The manufacture products, HS 28 – HS 39, HS 45 – HS 70, and HS 82 – HS 97; and oil, mining, mineral and metal products HS 25 – HS 27 and HS 72 – HS 81. The complete classification is shown in the Table 1. (This might be better put as appendix)
The trade data from Indonesia and China are used in the calculation such as export rate (base on Free on Board Price, FOB) and import rate (Cost, Insurance and Freight Price, CIF). The calculation of ICC is based on the data of 2005 and 2009. The aim of the calculation is to find the change of the ICC value within 5 years period. In addition, it will show the change of the trade flow between the two countries.
166 - Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011
Table 1. Classification of hS 2 Digit Products by Sectors
168 - Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011
Product Competitiveness in Indonesia-China Trade Relationship
The overview of the change in the ICC between Indonesia and China
is depicted in the Table 2. The empirical analysis using the ICC method shows that China has more competitiveness than Indonesia in general.
Table 2. Indonesia – China Total Trade ICC Change, 2005 – 2009
Source: UNCOMTRADE via WITS, 2010 (own calculation)
The ICC shows that Indonesian trade competitiveness declined because of the declining trade flow since 2007 and became minus in 2008. It actually started in 2005 where the Indonesian
trades balance in non oil and gas sector began to be minus (Figure 1). Indonesia’s total trade with China before 2008 enjoyed a trade surplus due to the large surplus in oil and gas.
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011 - 169
The ICC calculation explains that the change of the competitiveness of a country is caused not only by the change of its export activities but also import activities. It means that some product share may shrink but the others may expand. In other words each country has their special competitive product.
Agricultural Product CompetitivenessTable 3 describes the competitive-
ness of agricultural products between Indonesia and China. In over all, China’s agriculture products have more competitiveness than that of Indonesia. Fourteen products from China have positive changes during 2005 -2009, while Indonesian only has 11 products.
China is a net exporter for Cereals (HS 10) to Indonesia. The competitiveness of other products such as Products of animal origin (HS 05); Edible vegetables and certain roots (HS 07); Products of milling industry (malt, starches, etc) (HS 11); Lac, gums,
resins & other vegetable (HS 13) e; Prep of vegetable, fruit, nuts (HS 20); Beverages, spirits and vinegar (HS 22); Residues & waste from the food industry (HS 23); Articles of leather; saddlery/harnest (HS 42); and Fur skins and artificial fur (HS 43) have increased. The export values of the nine items have expanded.
China has good improvement in competitiveness for products such as Fish & crustacean, mollusc & other (HS 03); Live tree & other plant; bulb, root (HS 06); and Coffee, tea, mate and spices (HS 09). The performances of three products have shifted China from an importing to an exporting country. On the other hand, the values of imported products from Indonesia such as Oil seed, oleagi fruits; miscellaneous (HS 12) and Wood and articles of wood (HS 44) decreased. Their supplier countries could be shifted from Indonesia to others countries, especially ASEAN member.In agriculture sector, China is a net
Figure 1. Indonesian Non Oil and Gas Trade with China, 2004 -2010*
Source: Indonesian Statistics, 2010 (Calculated by Ministry of Trade)*) Estimation
3.4 4.05.5
6.77.8
8.9
14.1
3.44.6 5.5
8.0
14.913.5
19.7
0.1
-0.6 0.0-1.3
-7.2-4.6 -5.6
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
US$
Mili
ar
Ekspor Impor NeracaImport Trade Balance Export
US$
Bill
ion
170 - Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011
importer for Vegetable plaiting materials (HS 14) and Animal/vegetable fats & oils & their derivatives (HS 15). The HS 15 covers Crude Palm Oil (CPO), which
is the main product of Indonesian. Those products are used by China for producing food and cosmetics. The HS 14 includes bamboo and rattan.
Table 3. The Agriculture ICC: Indonesia – China, 2005 - 2009
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011 - 171
Meanwhile, Indonesia is a net exporter for product of Meat and edible meat offals (HS 02); Vegetable plaiting materials (HS 14); and Cocoa and cocoa preparations (HS 18). The HS 14 and HS 18 are other Indonesian main export products in Agriculture besides CPO. The export rate of Rubber and articles thereof (HS 40), especially natural rubber is significantly high in 2009, but in the same time import of rubber products from China is also high. The impact has no differences on the ICC from 2005 to 2009.
The reason that Indonesia’s Competitiveness in Agriculture product
Source: UNCOMTRADE via WITS, 2010 (own calculation)
is less than that of China because of the implementation of Early Harvest Program for ACFTA. This program is conducted for the Agriculture products for HS 01 – HS 08. The analysis showed the increasing import on Edible vegetables and certain roots (HS 07) and Edible fruit and nuts; peel of citrus (HS 08). This is why there are so many vegetables and fruits imported from China in the Indonesia.
Manufactured Product CompetitivenessThe analysis of ICC on
Manufacture Product showed that Indonesia has lost the Competitiveness
172 - Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011
since 2005. The Manufacture com-petitiveness condition forced the Indonesian government to rearrange the implementation of full ACFTA in 2010. The objective is to give opportunity to Indonesian industry to maintain their competitiveness and preparing after the market where opened. Indonesia asked for the postponement for 228 product items in the HS 10 digit level not to be included yet in the reduction of post tariff in ACFTA framework. These 228 products are considered as the industry which employs many workers and strategic industry for the country. Considering the cost to renegotiate for the 228 products that will be about US$ 1.2 billion and the obligation on ACFTA treaty that Indonesia should make notification to all “parties with supplying interest” (ASEAN member countries and China), Indonesia took a step to make another agreement (Yanuarti, Manuputty & Djafar, 2010; Pangestu, 2010).
Furthermore, the agreement took a point for both countries to rebalance the trade if there are any unbalances. The rebalance mechanism is conducted by maintenance the export and import volume. Indonesia get the commitment from China’s government to help the revitalization of the out date industry such as textile industry.
In the other hands, in some products as shows in Table 4 below Indonesia still have opportunities to expand the market. The export of The products such as F o o t w e a r , gaiters and the like; part (HS 64) have significantly increased for 158.5% for 2005/2009. The positive export performance of footwear products is impacted by the back relocation of many footwear industries, which in few years
has left, to Indonesia. The situation of footwear industries is predicted will be the same like Textiles and apparel industries as well. The China’s economic growth has increased the high wage rate. Many China’s industries have informed to relocate their manufacture to Indonesia.
The analysis in Manufactured Products found the suspicious trade activity. The trade of Arms and ammunition; parts and accessories (HS 93) might be done by illegal import to Indonesian market if there is no miss management of Indonesian Custom. The suspicious trade activity found because during 2005 and 2009 there are no export from china to Indonesia. But, Indonesian trade data noted that the import of HS 93 is US$ 2.6 million in 2005.
Oil, Mining and Mineral Products Competitiveness
The performance of Indonesian Oil, Mining, Mineral and Metal Product Competitiveness has no difference with the other sectors. Eventhough, the export of Oil mainly stabilize the trade in surplus until the end of 2008, but in general its competitiveness has declined in 2005/2009 period. In aggregate HS 2 digit, all products of the Oil, mining, mineral and metal show higher rate in import than export with China (Table 5).
Most of Indonesian products which have positive value on ICC are products based on the natural resources such as Ores, slag, ash, coal, Copper, and tin. The export performance corresponds to the China’s Policy import at natural resources. The Policy has impacted on the increased of world natural resource price in 2008 and 2009.
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011 - 173
Table 4. The Manufacture ICC: Indonesia – China, 2005 - 2009
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011 - 175
Source: UNCOMTRADE via WITS, 2010 (own calculation)
Concluding remarksThe trade relation between
Indonesia and China is giving more competitiveness for China. China’s products which have higher competitiveness than Indonesia such as Fish & crustacean, mollusc & other (HS 03); Live tree & other plant; bulb,
root (HS 06); and Coffee, tea, mate and spices (HS 09). Those products have performed China as importir toward exporter.
Even though, some Indonesian products have good competitiveness and develop the competitiveness during the period of 2005 to 2009. Other
176 - Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011
than CPO which is one the Indonesia main export product, Vegetable plaiting materials (including rattan and bamboo), the footwear, textiles and apparel products have increased the competitiveness. These products have expanded in China’s market during last five years.
The Indonesian government should launch the policy which could utilize “the Agreed Minutes of the Meeting for Further Strengthening Economic and Trade Cooperation”. The objective of the policy is not only to rebalance the trade performance but also to keep the competitiveness of the products in the other economics term. The activities would be useless if the policy don’t have effect on real work.
REFFERENCESPangestu, Mari Elka. 2010. Di Cina
Juga Ada yang Belum Siap. Tempo Online, Retrieved from http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/04/12/WAW/mbm. 20100412.WAW133238.id.html. accessed at February 18th, 2011 07:00 am.
Ministry of Trade, Republic of Indonesia. 2010. The Indonesian Ministry of Trade Pers Release, February 2010.
Tambunan, Tulus & Agustina Suparyati. 2009. ASEAN-China Trade Liberalisation Effect on Indonesian Agricultural Production and Trade. Policy Discussion Paper Series. Center For Industry. Sme & Business Competition Studies, Trisakti University. Retrieved from http://www.fe.trisakti.ac.id/pusatstudi_industri/pusat%20study %20tulus%20tambunan/pusat%20studi/policy%20discussion%20paper/pdf3.pdf. accessed at February 20th, 2011 08:00 pm.
World Integrated Trade Solution (WITS). 2011. Retrieved from http://wits.worldbank.org. accessed February 10th, 2011 09:00 pm.
Yanuarti, Astari, Cavin R. Manuputty, & Anthony Djafar. 2010. ACFTA: Mencari Keseimbangan Garuda-Naga. Ekonomi, Gatra, 26. Retrieved from http://web.gatra.com/versi_cetak.php?id=137497. accessed at February 18th, 2011 09:00 am.
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011 - 177
PENDAHULUANMerebaknya dominasi pelaku
usaha terhadap konsumen pengguna dikarenakan oleh penguasaan produk yang sepenuhnya berada pada produsen. Situasi yang tidak kon-dusif ini merupakan faktor penting diberlakukannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dan ini merupakan upaya pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan kepada para konsumen.
Jauh sebelum diberlakukannya UUPK, secara yuridis formal prinsip product liability sebenarnya telah
PENERAPAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK (STRiCT LiABiLiTy) DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN
Oleh :Yudha hadian Nur1
Dwi Wahyuniarti Prabowo2
Naskah diterima : 20 Juni 2011Disetujui diterbitkan : 12 Desember 2011
AbstractIndonesia’s population is about 235 million in 2010, which becomes a potential market for producers. However, these situations become a problem because of the low education and other social economic problems which cause exploitation on consumer. Although the Law no 8, year of 1999 on consumer protection was launched by the government, the law enforcement on consumer protection is still in question. One of the alternative solutions that can be raised is the regulation of the amendment of consumer protection law by adding the principles of strict liability. It should also include the design for the area of business to be enforced, including the producers who become the subject of the provision.
Keywords: strict liability, consumer protectionJEL Classification: K13
1 Peneliti Tingkat Pertama pada Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Jl. MI. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat, Telp. 021-23528692; Email: [email protected]
2 Calon Peneliti pada Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Jl. MI. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat, Telp. 021-23528692; Email: [email protected]
diatur dalam beberapa pasal dalam KUH Perdata, diantaranya Pasal 1322, 1473, 1474, 1491, 1504 sampai dengan 1511. Walaupun dengan catatan, ruang lingkup materinya tidak se-ekstensif ketentuan yang diatur dalam UUPK. Pada KUHPerdata secara umum apabila ada seorang yang melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) maka seseorang tersebut diwajibkan untuk memberikan ganti kerugian. Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan lima syarat suatu perbuatan dapat masuk dalam kualifikasi PMH, yaitu: (1) adanya perbuatan, (2) perbuatan tersebut melawan hukum, (3) adanya
178 - Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011
kerugian, (4) adanya kesalahan, dan (5) adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkannya. Semula hanya ada 4 unsur, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu perbuatan, melawan hukum, kerugian dan kesalahan, sebelum ditambahkan dengan unsur kausalitas. Kelima unsur tersebut harus dipenuhi karena bersifat kumulatif, jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka akan menyebabkan seseorang lepas dari tanggung jawab PMH. Kesulitannya pihak konsumen harus membuktikan adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha, agar gugatan konsumen tidak gugur/batal.Tanggung Jawab Produk menurut buku III KUH Perdata adalah tanggung jawab produk dari sudut hukum perikatan, terdiri dari dua macam yaitu: (a) tanggung jawab produk secara kontraktual; dan (b) tanggung jawab produk secara deliktual.
UUPK telah mengatur tentang product liability, namun dalam pelaksanaannya kurang efektif melindungi konsumen dari kerugian yang diakibatkan oleh suatu produk. Oleh karena itu dalam rangka dilakukannya amandemen UUPK, masalah strict liability menjadi konsep penting dan relevan untuk didiskusikan. Apakah dengan mencantumkan prinsip tanggung jawab langsung (strict liability) kepada produsen, UUPK akan lebih efektif? Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) itu sendiri dapat diartikan bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian konsumen tanpa harus membuktikan ada tidaknya kesalahan pada dirinya.
Metode analisis yang diper-gunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis, yaitu dengan menggunakan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai perangkat analisisnya. Data primer dikumpulkan melaui FGD, yang dilakukan di tiga propinsi, yaitu Provinsi Sumater Utara, Jawa Timur, dan Bali. Selain itu, analisis perbandingan juga dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan dengan prinsip tanggung jawab mutlak produsen yang diterapkan di Belanda.
Analisis dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama adalah menyusun tata urutan peraturan perundang-undangan yang terkait, kemudian memahami konstelasi peraturan perundang-undangan ter-sebut berdasarkan pada asas: lex superior derogat legi inferiori (ketentuan yang lebih tinggi mengenyampingkan ketentuan yang lebih rendah); lex specialis derogat legi generali (ketentuan yang lebih khusus mengenyampingkan yang lebih umum); atau lex posteori derogat legi priori (ketentuan yang lebih baru mengenyampingkan ketentuan yang lebih lama). Tahap ke dua, hasil analisis tahap pertama disampaikan pada FGD dengan para pakar, kemudian disempurnakan dengan berbagai informasi dan hasil pembahasan dalam FGD. Melalui tahapan ini diharapkan akan sampai kepada kesimpulan akhir, berupa usulan kemungkinan pencantuman dan penerapan prinsip strict liability dalam rancangan UUPK yang baru. Adapun alur pikir analisis yang dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam gambar Skema Kerangka Analisis dibawah ini.
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011 - 179
Konsep Perlindungan Konsumen di Indonesia
Indonesia dengan ratusan juta konsumen menjadi pasar yang sangat menarik bagi produsen. Persaingan semakin tinggi tanpa masyarakat mampu untuk melakukan kontrol yang efektif. Situasi ini menjadi sangat kondusif bagi lahirnya tekanan terhadap hak-hak konsumen.
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak yang sangat luas terhadap pola kehidupan manusia. Antara lain corak kebutuhan dan upaya pemenuhan kebutuhanpun mengalami peningkatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Korelasinya adalah muncul respons dari para pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan konsumen tersebut. Secara makro,
Gambar 1. Skema Kerangka Analisis
180 - Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011
kondisi ini menjadi warna dari dunia usaha pada umumnya.
1. Perlindungan Konsumen dalam Era Consumerism-wise di Indonesia
Perlindungan konsumen di Indonesia diawali dengan kelahiran Lembaga Konsumen Indonesia pada bulan Mei tahun 1973, sebuah lembaga yang bertujuan melindungi konsumen, menjaga martabat konsumen dan membantu pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk melindungi hak-hak konsumen telah muncul. Lembaga ini kemudian menjalankan fungsinya sebagai lokomotif yang menggerakan kesadaran konsumen maupun pelaku usaha.
Pada tanggal 20 April 1999, Indonesia pada akhirnya mempunyai Undang-Undang Perlindungan Kon-sumen (UUPK) sebagai dasar dalam penerakan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Undang-Undang ini diharapkan dapat menjadi alat dan acuan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha. Undang-Undang ini diharapkan dapat mendorong iklim berusaha yang sehat, serta lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan jasa yang berkualitas.
Dibandingkan dengan waktu sebelum ada UUPK, konsumen kita saat ini secara hukum sudah mendapatkan payung berupa undang-
undang untuk melindungi kepentingan mereka. Seluruh pasal yang termuat dalam UUPK mempunyai ciri khusus dibandingkan dengan peraturan dan ketentuan lainnya yang mengatur hal yang sama. UUPK lebih bernuansa adanya sikap keberpihakan kepada konsumen (consumerism wise) tanpa mengabaikan hak-hak pelaku usaha. Konsumen diberi hak dan kesempatan yang leluasa untuk mempertahankan kepentingannya. Hal ini mungkin bersifat reaktif atas fenomena dunia usaha yang didominasi oleh pelaku usaha. Dasar filosofi inilah yang secara yuridis menempatkan kedudukan UUPK menjadi lebih tegas dan jelas peruntukannya.3
2. hak dan Kewajiban KonsumenHak dan kewajiban secara
umum memiliki keterkaitan erat dengan lingkup perikatan, khususnya perjanjian. Sehingga permasalahan hak dan kewajiban dalam perlindungan konsumen memiliki suatu relevansi dengan permasalahan perdata, yang di Indonesia secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Menurut ketentuan umum dalam KUH Perdata, suatu perjanjian memang tidak harus dibuat secara tertulis, kecuali untuk perjanjian-perjanjian yang memang harus dibuat secara tertulis4. Ketentuan tentang syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3 Tria Sasangka Putra, S.H., LL.M., “Perlindungan Konsumen dalam Era Consumerism-Wise di Indonesia”, Harian Pelita. (12 Januari 2006)
4 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, PT Gramendia Pustaka Utama, Jakarta 2003, Cetakan ketiga, hal 26
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011 - 181
Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa No.39/248 tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen (Guidelines for Consumer Protection), juga merumuskan berbagai kepentingan konsumen yang perlu dilindungi, yang meliputi:5 a. perlindungan konsumen dari
bahaya-bahaya terhadap keseha-tan dan keamanannya;
b. promosi dan perlindungan kepen-tingan ekonomi sosial konsumen;
c. tersedianya informasi yang me-madai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;
d. pendidikan konsumen;e. tersedianya upaya ganti rugi yang
efektif;f. kebebasan untuk membentuk
organisasi konsumen atau orga-nisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka (Resolusi PBB No.39/248, 1985).
Jelas bahwa konsumen dalam UUPK juga merupakan komponen utama dalam suatu mekanisme penawaran dan permintaan atas suatu produk.
Namun demikian, konsumen jangan sampai diposisikan sebagai pihak yang pasif, melainkan harus turut aktif dalam menyikapi produk-produk yang beredar dipasaran yang dipergunakan oleh para konsumen.
3. Perlindungan hukum Bagi Kon-sumen di Indonesia
Dengan diundangkannya UUPK, maka bersama itu pula tercipta suatu kepastian hukum yang diberikan secara khusus kepada konsumen. Berbagai permasalahan konsumen telah diatur sedemikian rupa dalam undang-undang tersebut. Meskipun diduga masih terdapat kelemahan atau kekurangan tetapi setidaknya undang-undang ini dapat menjadi dasar perlindungan kepentingan para stakeholder. Beberapa jalur perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh para konsumen, yang secara umum adalah:
• Penerapan Prinsip Product Liability
Pada tanggal 1 Januari 1995, World Trade Organization (WTO) telah resmi berdiri menggantikan General Agreement of Tarrifs and Trade (GATT). Dengan demi-kian WTO merupakan organisasi
5 Pasal 3 UU No.8/1999, menyatakan bahwa perlindungan konsumen bertujuan untuk:a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif
pemakaian barang dan/atau jasa;c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya
sebagai konsumen;d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan
keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga
tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang, menjamin kelangsungan usaha produksi
barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
182 - Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011
antar pemerintah dunia yang mengawasi perdagangan dunia, baik perdagangan barang maupun jasa. Segala sesuatu yang berbau proteksi/perlindungan dianggap anti WTO atau anti liberalisasi perdagangan6. Dalam menghadapi kondisi semacam ini negara-negara di seluruh dunia telah mempersiapkan berbagai macam perangkat undang-undang perlindungan konsumen.
Dalam mengantisipasi produk-produk barang atau jasa yang merugikan atau mencelakakan konsumen, sebagian negara peserta perdagangan bebas telah menganut doktrin product liability dalam tata hukumnya. Seperti: Jepang, Amerika Serikat, dan Masyarakat Ekonomi Eropa serta negara-negara lain yang sudah terbiasa menjadikan hukum sebagai alat rekayasa sosial menuju kepastian hukum yang berkeadilan sosial. Terminologi product liability di Indonesia ada yang mengartikulasikannya sebagai tanggung jawab gugat produk.
UUPK mengatur tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen yang secara khusus dimuat dalam satu bab, yaitu Bab VI, mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28. Dari kesepuluh pasal tersebut, dapat kita pilah sebagai berikut: a. Tujuh pasal, yaitu pasal 19,
pasal 20, pasal 21, pasal 24, pasal 25, pasal 26, dan pasal
27 yang mengatur tentang pertanggungjawaban pelaku usaha;
b. Dua pasal yang mengatur tentang pembuktian, yaitu pasal 22 dan pasal 28
c. Satu pasal yang mengatur penyelesaian sengketa jika pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya memberikan ganti rugi.Asumsinya adalah terhadap
pelaku usaha yang bertindak sedemikian rupa dan dengan memperhatikan telah terpenuhinya unsur-unsur dari product liability, maka terhadapnya dapat diproses penyelesaian sesuai dengan jalur hukum yang telah disediakan oleh UUPK.
• Penerapan Prinsip Strict Product Liability
Sebenarnya dalam kasus terkait prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha dapat dipertanyakan tentang intervensi pemerintah, dalam memberikan jaminan terhadap hak-hak konsumen, khususnya terhadap keselamatan, kesehatan, dan hak untuk mendapatkan ganti kerugian, baik berupa cacat atau kerusakan pada tubuh konsumen (bodily/personal injury), maupun kerusakan yang berkaitan dengan produk itu sendiri (pure economic loss)7.
Prinsip tanggung jawab mutlak (strict product liability) merupakan prinsip tanggung jawab yang tidak
6 Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, PT Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-II, 2003, hal 8
7 Inosentius Samsul, “Ringkasan Disertasi Prinsip Tanggung Jawab Mutlak”, Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2003, hal-22.
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011 - 183
didasarkan pada aspek kesalahan (fault/negligence) dan hubungan kontrak (privity of contract), tetapi didasarkan pada cacatnya produk (objective liability) dan risiko atau kerugian yang diderita konsumen (risk based liability). Dikatakan bahwa tujuan utama dari prinsip tanggung jawab mutlak adalah jaminan atas konsekuensi atau akibat hukum dari suatu produk yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen8.
Latar belakang penerapan tanggung jawab mutlak dimaksud adalah pemikiran bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menjamin bahwa produk tersebut 100% aman untuk dikonsumsi. Meskipun demikian, prinsip strict product liability ini masih belum diterapkan di Indonesia, tetapi peluang untuk itu masih terbuka, mengingat baik produsen maupun konsumen beritikat untuk mendapatkan hak mereka dalam perlindungan hukum.
Selanjutnya penyelesaian seng-keta yang diatur dalam UUPK adalah melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Dalam UUPK Pasal 45 Bab X. Disebutkan bahwa sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui pengadilan ataupun luar pengadilan ber-dasarkan pilihan sukarela dari para pihak. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 45 tersebut antara
lain:a. Adanya kerugian yang diderita
oleh konsumen b. Gugatan dilakukan terhadap
Pelaku Usaha c. Dilakukan melalui pengadilan.
Pasal 48 UUPK menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam peradilan umum dengan memperhatikan ketentuan pasal 45 UUPK. Selain itu, menurut ayat (1), pasal 48 penyelesaian sengketa dapat pula dilakukan diluar jalur pengadilan. Penyelesaian diluar jalur pengadilan ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana bunyi pasal 49 sampai dengan pasal 58 UUPK9.
Selain itu, berdasarkan penjelasan pasal 45 ayat (2), penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat pula dise-lesaikan melalui jalan damai oleh mereka yang bersengketa, tanpa melalui pengadilan ataupun BPSK. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak boleh menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur pasal 45 ayat (3). Pasal 62 ayat (3) dengan jelas menetapkan bahwa tanggung jawab pidana harus dipertanggung jawabkan oleh pelaku usaha, diperiksa dan
8 Inosentius Samsul, Hukum Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, Cetakan 1 – Jakarta, 2004, hal-227
9 Heri Tjandrasari, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dan Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen, 05 Jun 2003, 14:00:15 WIB - pemantauperadilan.com, http://www.pemantauperadilan.com/detil/detil.php?id=93&tipe=opini
184 - Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011
diselesaikan menurut ketentuan pidana yang berlaku.
Sebagai upaya untuk mem-permudah konsumen dalam memperoleh hak-haknya yang dilanggar ataupun dirugikan oleh pelaku usaha, pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan berupa Keputusan Presiden maupun Keputusan Menteri Per-industrian dan Perdagangan Republik Indonesia. Dari beberapa Keputusan tersebut yang terpenting diantaranya adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Keputusan Menteri Perindustrian dan Per-dagangan Republik Indonesia Nomor 301/MPP/Kep/10/2001 tentang Pengangkatan Pember-hentian Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
UU perlindungan konsumen di Indonesia sudah menyediakan saluran-saluran hukum untuk para konsumen untuk menuntut haknya apabila terjadi ketidak-jujuran produsen ataupun importir. Melalui saluran BPSK, konsumen diberikan kesempatan untuk menuntut pihak produsen terhadap cacatnya produk maupun kerugian
4. Lemahnya Kedudukan Konsu-men di Indonesia
Harus diakui bahwa tidak semua produsen memahami kewajiban yang seharusnya mereka lakukan dalam melindungi konsumen. Masih banyak pengusaha yang mengesampingkan kepentingan hakiki konsumen untuk mendapatkan produk berkualitas baik dan menyehatkan.
Pada kenyataannya, terdapat perbedaan yang nyata antara ketentuan hukum dan praktek di lapangan. Produsen lebih menekankan pada keuntungan dan dan dengan segala cara berusaha menaikan omzet dari usaha yang mereka lakukan. Dilain pihak, konsumen kurang mendapatkan informasi yang cukup tentang produk yang mereka pergunakan. Berbagai peristiwa yang terjadi, seperti keracuanan masal, kematian akibat mengonsumsi produk tertentu, dan sebagainya sering kurang diinformasikan secara transparan. Padahal, konsumen dapat memberi keuntungan besar kepada produsen.
UUPK dan perangkat peraturan lainnya yang berupaya mengoptimalkan perlindungan terhadap konsumen, dalam hal ini belum optimal. Hukum masih terasa kurang menyentuh dan berpihak kepada konsumen. Oleh karena itu, optimalisasi efektifitas perangkat hukum merupakan hal yang mendesak yang perlu segera dilakukan.
Informasi yang jelas tentang spesifikasi suatu produk merupakan indikator itikad baik produser. Berdasarkan hukum, produsen yang telah melakukan tindakan tersebut akan mendapatkan reservasi tersendiri bilamana terdapat gugatan seputar dampak negatif yang ditimbulkan oleh
yang dideritanya.
produk-produk mereka.
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011 - 185
Prinsip Tanggung Jawab Produk (Product Liability)
Secara umum tanggung jawab produk ialah tanggung jawab produsen untuk produk yang telah diedarkannya, yang menimbulkan atau mengakibatkan kerugian akibat misalnya cacat yang melekat pada produk tersebut. Selanjutnya dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa tanggung jawab yang dimaksud disini meliputi tanggung jawab kontraktuil atau berdasarkan perjanjian dan tanggung jawab perundang-undangan berdasarkan perbuatan melanggar hukum. Pengertian produsen dari definisi tersebut adalah produsen (pembuat), grosir (wholesaler), leveransir dan pengecer (retailer) profesional. Produk disini meliputi benda bergerak maupun tidak bergerak yang telah dipasarkan oleh produsen. Kerugian yang dimaksud dengan definisi di atas adalah kerugian yang ditimbulkan atau disebabkan oleh produk dan kerusakan atau musnahnya produk. Sedang pengertian cacat yang melekat pada produk adalah kekurangan pada produk yang menjadi penyebab timbulnya kerugian.
Ada perbedaan pengaturan tanggung jawab produk di beberapa negara. Di negara-negara kodifikasi biasanya penga turan tanggung jawab produk merupakan bagian daripa da hukum perikatan khususnya hukum perbuatan melanggar hukum. Ada negara yang menempatkan pengaturan daripada tang gung jawab produk dalam hukum konsumen atau hukum perlindun-gan konsumen. Se dangkan pandangan yang paling progresif melihat pengaturan tanggung jawab produk sebaiknya diatur dalam hukum yang tersendiri, yakni "Product Liability Law." Dari berbagai perbedaan pengaturan tersebut dapat
disimpulkan bahwa hukum tanggung jawab produk merupakan fenomena baru yang belum jelas pengaturan-nya. Namun pada umumnya, tanggung jawab terhadap suatu produk bermula dari hukum perikatan.
Di Indonesia, sebagaimana dengan negara kodifikasi hukum, tanggung jawab produk merupakan bagian dari hukum perikatan. Selain dari pengaturan tersebut hukum tanggung produk di Indonesia juga sudah banyak diatur dalam undang-undang maupun peraturan perlindungan konsumen lainnya. Namun kontrol penaatan peraturan-peraturan tersebut masih sangat kurang, sehingga peraturan-peraturan tersebut menjadi kurang berfungsi. Masalah tersebut terjadi karena masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia dan sikap pemerintah yang lebih melindungi dunia industri sebagai bagian dari kebijaksanaan ekonomi.
Beberapa Kasus Dampak Negatif Suatu Produk
Penerapan strict liability di Indonesia tidak semata-mata muncul tanpa adanya suatu sebab apapun juga. Pada bagian ini, penulis memberikan beberapa contoh dari sekian banyak permasalahan yang berkenaan dengan dampak yang ditimbulkan oleh produk-produk yang beredar di masyarakat. Beberapa kasus yang ada diantaranya adalah:
1. Kasus Ledakan Tabung Gas LPGMaraknya kasus ledakan tabung
gas LPG, menjadi salah satu bukti nyata dari buruknya upaya perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa yang beredar di masyarakat. Program konversi minyak tanah ke gas di satu
186 - Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011
sisi mampu menghemat subsidi bahan bakar minyak, namun di sisi lain, penggunaan gas LPG justru memakan korban dan menimbulkan kerugian material yang cukup besar terhadap konsumen, pemerintah maupun pelaku usaha.
Seperti diketahui bahwa, saat ini kasus meledaknya tabung gas LPG marak terjadi, terutama untuk jenis
tabung gas 3 Kg. Berdasarkan data dari litbang Kompas dan PT Pertamina, jumlah kasus yang terjadi dari tahun 2008 hingga Juli 2010 mencapai 52 kasus, dengan total korban tewas mencapai 30 jiwa dan 113 korban luka-luka. Selain itu, kerugian yang diderita oleh konsumen antara lain rumah rusak, rumah terbakar hingga kendaraan
Sumber: Litbang Kompas dan PT Pertamina (Persero), 2010.Ket: *) hingga 28 Juli 2010.
Tabel 1. Kasus Ledakan Tabung Gas LPG
rusak.
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011 - 187
Berdasarkan Surat Wakil Presiden No. 28/WP/XI/2006 tanggal 8 November 2006, pada awalnya PT Pertamina hanya diberi tugas dalam pengadaan tabung. Sementara, pengadaan kompor dan regulator diserahkan kepada KUKM. Namun, sejak 2007 hingga sekarang PT Pertamina bertanggung jawab penuh pada pengadaan tabung, kompor berikut regulator (Primair Online, 6 Juli 2010).
Pemerintah menyatakan bahwa seluruh kerugian akibat kecelakaan penggunaan gas LPG 3 kg ditanggung pemerintah. PT Pertamina menanggung semua biaya pengobatan korban ledakan gas. Selain itu, Pertamina juga akan memberikan ganti rugi terhadap kerugian harta benda yang rusak akibat
Ganti rugi oleh Pertamina dilakukan antara lain melalui sistem asuransi, dengan membayar premi untuk pengguna gas LPG paket perdana program konversi minyak tanah ke gas bagi kelompok prasejahtera. Sedangkan Kementerian Kesehatan memfasilitasi non teknis dan administrasi penanganan korban di rumah sakit. Pengguna gas LPG 3 kg paket perdana di Indonesia berjumlah 45 juta. Selain pemberian asuransi, Pertamina menyalurkan rubber seal (karet gas) ke seluruh stasiun pengisian bahan bakar LPG (SPBE) dan mengupayakan penggantian selang penyalur gas LPG substandar masyarakat sasaran program konversi minyak tanah ke gas (Litbang Kompas
Tabel 2. Instansi Terkait Pengawasan LPG
Sumber: Puska PDN Kemendag (diolah dari berbagai sumber)
ledakan tabung gas tersebut.
dan PT Pertamina (Persero), 2010)
188 - Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011
2. Kasus Susu Mengandung Mela-mine
Berita mengenai racun di bahan melamine kembali menyeruak pada pasca pertengahan tahun 2008 setelah kasus susu di China,. Ribuan bayi di China dikabarkan telah menderita berbagai penyakit yang disebabkan oleh kontaminasi melamine pada susu bubuk bayi. Banyak diantaranya berakibat fatal, dari mulai gagal ginjal hingga korban jiwa.
Di Indonesia berita tentang pengaruh negatif dari peralatan berbahan melamine meledak setelah pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan pengujian terhadap 62 peralatan makan dari melamine. Dari hasil pengujian tersebut ditemukan 30 antaranya melepaskan formalin apabila peralatan tersebut digunakan untuk tempat makanan yang berair, berasa asam terlebih dalam keadaan panas. Penggunaan peralatan makan dari bahan melamine dalam jangka panjang dapat beresiko menimbulkan gangguan ginjal dan kandung kemih, gagal ginjal, kerusakan organ tubuh, dan kanker (www.beritanet.com).
Menurut Direktur Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya BPOM, faktor penting penyebab peralatan berbahan dasar melamin dalam kondisi tertentu bisa melepaskan formalin adalah teknologi proses pembuatannya yang kurang baik. Untuk dapat menjamin keamanan peralatan berbahan melamin yang telah berdar di pasaran, BPOM berencana mengulas penandaan keamanan perangkat makanan berbahan dasar melamin
3. Kasus Kosmetik Mengandung Merkuri
Badan POM kota Jayapura menemukan kosmetik dengan berbagai merek mengandung bahan berbahaya antara lain berupa Merkuri (Hg) atau air raksa. Keduanya termasuk ke dalam golongan logam berat berbahaya, Merkuri walaupun dalam konsentrasi kecil, bersifat racun, menimbulkan efek buruk bagi kulit manusia, mulai dari perubahan warna kulit hingga alergi dan iritasi. Dalam jangka panjang penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya berdampak pula pada kerusakan permanen susunan syaraf, otak, ginjal serta gangguan pada perkembangan janin (www.tabloidjudi.com).
Untuk memberikan efek jera bagi para produsen, distributor hingga ke pengecer, Badan POM menerapkan beberapa pendekatan. Pertama pendekatan persuasif bersifat himbauan. Namun kelak jika ditemukan masih terulang, akan diterapkan pendekatan kedua, yakni cara represif projusticia. Adapun ketentuan pidana terkait permasalahan ini diatur dalam dua Undang-Undang. Pertama, Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Aturan ini ditujukan bagi yang memproduksi atau mengedarkan kosmetik mengandung bahan berbahaya. Sedangkan yang mengedarkan kosmetik tanpa ijin edar diancam pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 140 juta rupiah. Kedua, Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan
10 http://www.beritanet.com/Education/Info-Melamin-Formalin.html
dengan instansi tekait.10
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011 - 189
konsumen. Pelakunya akan diancam pidana penjara 5 tahun atau denda paling banyak 2 milyar rupiah.11
4. Kasus Bahan Bakar Premium Bermasalah
Beberapa pabrikan otomotif yang produknya terkena dampak premium bermasalah di Jakarta menurunkan tim untuk memeriksa penyebab kerusakan pada perangkat fuelpump, yang dikeluhkan angkutan umum, khususnya taksi di ibu kota. Pabrikan Chevrolet yang menjual produk Louva, yang digunakan untuk angkutan taksi, menurunkan timnya untuk memeriksa penyebab kerusakan bagian bahan bakar kendaraan itu. Hasil pemeriksaan dan survey yang dilakukan, menemukan partikel seperti pasir, sulfur, dan kadar timbal di atas normal. Kendaraan yang terkendala tidak hanya kendaraan yang sudah tua, namun juga kendaraan-kendaraan terbaru dari beberapa pabrikan ikut terkena dampaknya.12
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan berdasarkan hasil penelitian sementara, premium yang dijual PT Pertamina (Persero) sudah sesuai spesifikasi yang ditetapkan. Penurunan kualitas premium mungkin terjadi saat ditimbun di tangki Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Berdasarkan hasil penelitian sementara di empat titik, sebagian besar dari 11
kriteria, seperti angka oktan, kandungan sulfur, dan kandungan air, sudah sesuai ketentuan. Diduga penyebab menurun-nya kualitas premium adalah tangki SPBU yang kotor. Dalam jangka pendek, perubahan angka oktan dari 90 ke 88 tidak menyebabkan kerusakan pompa bahan bakar (fuel pump) mobil. Namun, untuk jangka panjang, perubahan angka oktan bisa merusak mesin (www.koran-jakarta.com).
Sementara itu, Kementerian ESDM belum mengetahui hasil penelitian laboratorium di Thailand yang menyebutkan bahwa kandungan sulfur premium Pertamina melebihi ambang batas. Sebelumnya, Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas menyatakan uji petik premium akan dilakukan pekan ini. Uji petik dilakukan menyusul merebaknya kasus kerusakan pompa bensin (fuel pump) pada ribuan kendaraan pribadi dan taksi di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Uji petik premium ini penting, mengingat kasus keusakan
11 http://tabloidjubi.com/index.php/edisi-cetak/advertorial/2090-peredaran-kosmetik-berbahaya-di-papua-memprihatinkan
12 http://regional.kompas.com/read/2010/07/26/17413943/Pabrikan.Turunkan.Tim.Uji.BBM.Bermasalah
13 http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=5835114 Wawancara dengan Joseph W. Chung, Kamer Van Koophandel, Maastricht, Prof. Jan van Dalen dari
Maastricht University dan perwakilan dari Consumenten Bond, Den Haag, 10 – 16 Oktober 2010
fuel pomp tidak terjadi di daerah lain.13
Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Di Belanda14
Perlindungan konsumen di Belanda telah berjalan akibat tingkat kesadaran hukum masyarakatnya telah sangat tinggi, sehingga kecurangan terhadap praktek jual beli lazimnya tidak terjadi, dan apabila ternyata produk yang dibeli tidak berfungsi ataupun tidak
190 - Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011
sebagaimana mestinya, pembeli dapat kembali kepada penjual dan meminta ganti. Artinya, apabila pembeli dapat memberikan bukti-bukti pembelian, maka pemilik toko berkewajiban untuk mengganti barang atau mengembalikan uang senilai dengan harga barang yang dibelinya.
Belanda sebagai salah satu anggota dari masyarakat Uni Eropa berupaya semaksimal mungkin menjaga produk-produk/barang-barang yang di-pasarkan di lingkungan negara-negara anggota Uni Eropa. Belanda, demikian juga negara-negara Uni Eropa lainnya, secara ketat melakukan pengawasan terhadap harga, kualitas dan standar produk.
Perlindungan konsumen dalam tatanan contract law berbasis pada hukum perdata, perikatan dikarenakan timbulnya hak dan kewajiban berdasarkan hubungan kontraktual dimaksud. Sedangkan, lingkup lainnya yang mencakup perlindungan konsumen termasuk dalam tatanan consumer sales. Belanda mengacu pada standar peraturan perlindungan konsumen yang diberlakukan di masyarakat Uni Eropa. Selanjutnya hukum perlindungan konsumen pun masuk dalam pranata hukum publik, mengingat konsumen dari produk-produk/barang-barang yang dipasarkan dipergunakan secara massal oleh masyarakat. Implikasi terhadap dampaknya pun terbuka kemungkinan dirasakan oleh banyak orang. Oleh karena itu, di Belanda diberlakukan hukum tentang makanan (food law), khususnya terhadap consumer goods product.
Dalam hukum perdata Belanda ditegaskan bahwa produsen bertanggung jawab atas kerusakan barang. Perlu disampaikan pula bahwa
tanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh suatu produk ditentukan besarannya secara pasti. Artinya, penggantirugian diperhitungkan berdasarkan kerugian material dan bukan berdasarkan perhitungan yang bersifat imaterial. Seorang konsumen tidak dapat meminta gantirugi berdasarkan perhitungan kerugian imaterial, karena hal tersebut tidak dibenarkan berdasarkan hukum yang berlaku Belanda. Penghitungan atas kerugian material yang diderita dapat dilakukan dengan cara memperhitungkan kerugian seseorang selama tidak dapat bekerja, memperbandingkan keadaan pada saat terjadinya musibah dengan kondisi terkini si korban.
Perlindungan konsumen di Belanda menekankan juga pada perlindungan atas perjanjian yang tidak seimbang. Perjanjian yang tidak seimbang atau merugikan konsumen tersebut harus dapat dibuktikan bahwa memang terdapat penyimpangan. Apabila tidak dapat dibuktikan maka produsen maupun distributor produk/barang tidak dapat dipersalahkan.
Informasi produk yang harus sesuai antara kandungan dan informasi yang dinyatakan merupakan suatu keharusan, bahkan merupakan suatu kemutlakan. Dengan kata lain tidak ada pengecualian berkenaan dengan keharusan yang dimaksud. Terutama hal yang dihindari adalah apabila informasi yang dinyatakan tersebut tidak sesuai dengan faktanya.
Belanda dalam hal ini memberlakukan ketentuan tanggung jawab produk dalam lingkup yang sangat detail dan terperinci, sehingga cukup dengan menegakkan peraturan-peraturan tentang tanggung jawab produk permasalahan sengketa
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011 - 191
perniagaan yang mungkin muncul dapat dihindari. Ketika peraturan yang detail tentang prinsip tanggung jawab produk telah berhasil dan efektif diterapkan, maka tidak ada alasan untuk memberlakukan prinsip strict liability. Peraturan yang ditali dan efektif dalam hal ini merupakan kekuatan tawar untuk tidak memberlakukan prinsip strict liability. Yang harus dipastikan adalah bahwa produk-produk yang beredar di pasar Belanda adalah produk-produk yang terjamin keamanannya, dilakukan pengawasan terhadap produk-produk yang beredar secara berkelanjutan, penyuluhan dan sosialisasi yang berkelanjutan dan kesesuaian antara informasi dalam label produk dan realitas produk.
Faktor keamanan atas produk merupakan faktor utama yang harus senantiasa diperhatikan. Tujuannya adalah untuk meminimalisir terjadinya kerugian maupun insiden yang akan dialami oleh konsumen. Salah satu bidang yang sangat kompleks dalam penanganan perlindungan konsumen adalah bidang makanan. Untuk itu diperlukan hukum tersendiri. Hukum tentang makanan tersebut terintegrasi erat dengan hukum perlindungan konsumen.
Sektor makanan di Belanda dan di Eropa pada umumnya merupakan satu sektor yang sangat diperhatikan mengingat produk tersebut langsung dikonsumsi oleh manusia dan jika terjadi kesalahan maka dampaknya dapat secara langsung dirasakan oleh orang-orang yang mengonsumsinya. Belanda memiliki complaint committee yang bertugas untuk menerima berbagai macam keluhan dari para konsumen, sekaligus sebagai kontrol terhadap
Di Belanda upaya penyelesaian perkara sengketa konsumen pada umumnya tidak menggunakan jalur pengadilan. Alasan utamanya adalah biaya pengacara yang mahal dan proses peradilan yang lama. Jalur peradilan merupakan pilihan terakhir yang ditempuh oleh para pihak yang berselisih.
Terbuka kemungkinan terdapat kekosongan hukum dalam kasus perlindungan konsumen akibat dari sifat khusus dari perkara yang terjadi. Apabila yang demikian ini terjadi, maka cara yang ditempuh adalah dengan mencari hukum yang relevan sebagai hukum yang paling baik untuk diterapkan. Seperti halnya hukum di Indonesia, hakim di Belanda dapat menentukan hukum yang digunakan untuk mengisi kekosongan hukum yang dimaksud.
Produsen wajib menyatakan bahwa produk tersebut tidak atau mengandung bahan-bahan yang berbahaya dan membahayakan. Secara spesifik dapat disampaikan bahwa aspek yang penting untuk selalu diperhatikan dan dianalisis oleh konsumen adalah tata cara yang seharusnya dalam menggunakan produk, dan tata cara memproduksi produk/barang yang paling baik (dari sisi produsen).
Meskipun di Belanda sudah diberlakkukan ketentuan tentang tanggung jawab produk, konsumen di negara ini tetap dapat menuntut ganti rugi terhadap produsen/pelaku usaha tanpa melalui proses persidangan, pembuktian terbalik maupun proses lainnya. Produsen/pelaku usaha harus membayar ganti rugi terhadap konsumen atas kerugian yang dideritanya, terutama apabila kerugian tersebut berkaitan dengan badan dan
produsen yang beritikad kurang baik. jiwa manusia.
192 - Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011
Pemberlakuan strict liability di Eropa secara garis besar didasarkan pada kebutuhan negara yang bersangkutan, perilaku dari masyarakat negara yang bersangkutan dan budaya hukum yang melatarbelakanginya. Beda negara berbeda pula permasalahan yang dihadapi. Namun demikian penekanan yang harus diperhatikan adalah masalah perlindungan hak konsumen dan produsen, serta aspek-aspek yang mendukung meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara.
Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability)
Saat ini, prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) sudah waktunya diterapkan di Indonesia. Pemberlakuan tanggung jawab mutlak ini sangat mendesak terkait dengan tingginya resistensi dari para produsen, tidak beritikad baik dalam berbisnis, dan banyaknya peristiwa yang menunjukan konsumen tidak dilingdungi secara maksimal. Indonesia merupakan pangsa pasar yang besar, baik bagi produsen lokal maupun internasional. Namun demikian, hak-hak konsumen di tempat ini belum mendapat perlingungan secara maksimal. Kasus-kasus seperti keracunan makanan, susu yang mengandung melamin, bensin tercemar, tabung gas yang meledak, kosmetik beracun dan lain sebagainya merupakan bukti dari kurangnya perlindungan tersebut.
Bagi sebagian besar produsen, konsumen hanya menjadi sumber pendapatan dan keuntungan. Mereka umumnya tidak menaati peraturan perundang-undangan mengenai kea-manan produk, tata cara pembuatan produk yang benar, tidak mencantumkan informasi produk pada label, dan
mematuhi berbagai macam ketentuan bidang perlindungan konsumen.
Tidak pula dapat dipungkiri bahwa masyarakat menghendaki produk-produk tertentu dalam harga yang relatif terjangkau, tetapi seharusnya permintaan pasar ini tetap harus disikapi dengan penuh tanggung jawab oleh para produsen. Peristiwa-peristiwa pelanggaran maupun penyimpangan seperti yang telah disampaikan di atas jarang terjadi di negara-negara Eropa maupun di negara-negara maju lainnya, selain karena adanya itikat baik dari produsen, juga karena adanya pengawasan yang ketat dan sanksi berat. Untuk melindungi konsumen, Indonesia telah memiliki peraturan perundangan tentang tanggung jawab produk, namun demikian, sebagaimana diuraikan di atas, belum berfungsi secara optimal.
Beberapa contoh kasus seperti halnya ledakang tabung gas, susu yang beracun di atas tidak seharusnya terjadi. Pertanyaannya adalah bagaimana Indonesia dapat meminimalisir penyim-pangan-penyimpangan, pelanggaran-pelanggaran atau bahkan kejahatan-kejahatan terhadap konsumen? Penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh. Dengan prinsip ini, produsen yang tidak bertanggung jawab akan mendapatkan sangsi yang berat.
Pelaku usaha beranggapan bahwa jika diberlakukan peraturan baru maka akan menimbulkan beban biaya baru bagi mereka, yang pada akhirnya mempengaruhi biaya produksi. Hal ini akan membebani konsumen. Seharusnya alasan klasik ini perlu disikapi, yaitu sampai sejauh mana beban biaya yang dinyatakan oleh
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011 - 193
para produsen tersebut adalah benar. Jika biaya tersebut bisa melindungi kepentingan konsumen dan sepanjang masih dalam batas-batas kewajaran maka seharusnya bukan merupakan masalah.
Pemberlakuan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) di Indonesia belum bisa diberlakukan untuk semua bidang usaha ataupun terhadap semua produk, tetapi hanya diberlakukan atas kelompok produsen dan produk tertentu . Diantaranya adalah produk-produk yang (a) risiko penggunaan produk; (b) tingkat kelalaian yang dilakukan oleh produsen; (c) produk-produk yang dipergunakan secara massal, dan lain sebagainya. Selain itu, produsen skala konglomerasi merupakan kelompok produsen yang mutlak harus menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak.
Kategorisasi tersebut di atas tidak ditujukan untuk melakukan diskriminasi, tetapi yang perlu dipahami bersama adalah produsen-produsen besar seharusnya telah memiliki sistem yang lebih baik. Oleh karena itu produsen yang bersangkutan seharusnya memiliki tanggung jawab yang lebih tinggi atas produk sesuai dengan reputasinya, dengan tujuan antara lain adalah sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada para konsumennya. Alasan lain adalah agar produsen-produsen besar dapat menjadi contoh yang baik bagi produsen-produsen kecil dan menengah dalam hal taat hukum, standarisasi, pelayanan, tanggung jawab produk, dan lain sebagainya. Dengan demikian, diharapkan kondisi yang kondusif yang mendorong tumbuh suburnya dunia industri yang sehat dapat terwujud.
Perlu untuk ditegaskan kembali bahwa prinsip tanggung jawab mutlak
(strict liability) merupakan pasal yang sangat berat untuk diberlakukan, karena dampakhukum yang akan diterima oleh produsen. Keadaan yang demikian ini justru akan menciptakan suatu kondisi yang kontraproduktif. Salah satu alternatif solusi yang dapat diajukan adalah melakukan amandemen UUPK, yang memungkinkan diterapkannya prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability).
KESIMPULAN
KesimpulanPerlindungan konsumen me-
rupakan salah satu bidang yang dinamikanya sangat pesat dan para stakeholder-nya memiliki kekerapan hubungan yang sangat intense. Demikian pula lingkup problematikanya yang juga mengalami perubahan yang sangat pesat. Hubungan-hubungan yang terjadi antar para stakeholder-nya adalah hubungan yang dikarenakan faktor kebutuhan (baik pokok, sekunder maupun tersier), ketersediaan pena-waran dan permintaan, pemasaran dan alur distribusi, pelayanan purna jual, keterbukaan informasi dan standarisasi yang benar atas suatu produk, etika dan tanggung jawab produsen dan konsumen, serta masih banyak lainnya. Deskripsi ini memberikan suatu pemahaman, bahwa yang perlu diatur adalah perilaku dan sikap tindak dari produsen dan konsumen agar tercipta suatu harmonisasi, ketertiban, keadilan dan kepastian. Apabila menyikapi begitu banyaknya deviasi, penyimpangan dan pelanggaran yang mengarah pada bentuk manipulasi maupun kriminalisasi terstruktur, maka momentum ini merupakan saat yang tepat untuk melakukan amandemen UUPK.
194 - Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011
Walaupun UUPK telah berlaku tetapi seringkali perkara yang diajukan ke pengadilan masih memperguna-kan ketentuan-ketentuan berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHPerdata. Hal ini mengindikasikan bahwa aparat penegak hukum belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang dalil-dalil hukum yang terdapat dalam UUPK untuk dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan dalam perkara-perkara sengketa konsumen. Hal tersebut diperparah dengan belum adanya persepsi yang sama diantara atau sesama aparat penegak hukum terhadap UUPK.
Sulitnya menemukan perkara perselisihan product liability dan strict liability di pengadilan Indonesia karena para pihak yang bersengketa lazimnya menggunakan mekanisme sengketa perdata umum dan bukan melalui lembaga penyelesaian perselisihan sengketa konsumen.
RekomendasiStrict liability jika dimasukkan
dalam perundang-undangan memiliki implikasi konsekuensi yang mem-beratkan produsen. Apabila ketentuan ini akan diberlakukan di Indonesia, maka beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan, yaitu meliputi: • pemberlakuannya hanya untuk
kelompok-kelompok produsen ter-tentu;
• produk-produk yang mengandung bahan berbahaya;
• intensitas kelalaian produsen yang sangat tinggi dalam menentukan standar maupun kualitas barang;
• produk-produk yang dipergunakan secara massal;
• produk-produk yang bersentuhan
• produsen-produsen yang termasuk kategori konglomerasi ataupun produsen berskala besar.
Salah satu alternatif solusi yang dapat diajukan adalah dengan mengatur dalam amandemen UUPK, bahwa UUPK mengatur tentang prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) dan ketentuan lebih lanjut tentang prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah/peraturan pelaksana.
Apabila dalam agenda amandemen UUPK tidak dimasukkan mengenai pemberlakuan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability), maka kewajiban bagi para perancang kebijakan untuk menjadikan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tanggung jawab produk menjadi lebih ekstensif dan komprehensif muatannya atau bahkan ketentuan mengenai sanksi maksimal yang diberikan harus memberikan efek jera bagi mereka yang melakukan pelanggaran.
DAFTAR PUSTAKA
Anonim.(2009). “Info Lengkap Soal Melamin dengan Formalin”. Diunduh dari http://www.beritanet.com/Education/Info-Melamin-Formalin.html tanggal 7 Juni 2010.
Anonim.(2009). “Peredaran Kosmetik Berbahaya di Papua Memprihatinkan”. Diunduh dari http://tabloidjubi.com/index.php/edisi-cetak/advertorial/2090-tanggal 13 Juni 2010
Anonim.(2010). “Pabrikan Turunkan. Tim. Uji. BBM. Bermasalah”. Diunduh dari http://regional.kompas.com/
langsung dengan manusia; dan
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011 - 195
read/2010/07/26/17413943/ pada tanggal 15 September 2010,
Anonim.(2010). Diunduh dari http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=58351 pada tanggal 21 September 2010,
Kompas. (2010). Pertamina Bantu Korban Ledakan Gas. Litbang Kompas dan PT Pertamina (Persero), Kompas, 28 Juli 2010.
Putra, Tria Sasangka. (2006). “Per-lindungan Konsumen dalam Era Consumerism-Wise di Indonesia”, Surat Kabar Harian Pelita, 12 Januari 2006.
Samsul, Inosentius. (2004). Hukum Perlindungan Konsumen Ke-mungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak. Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, Cetakan 1 – Jakarta, 2004
Samsul, Inosentius. (2003). Ringkasan Disertasi Prinsip Tanggung
Jawab Mutlak Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Univer-sitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana.
Shofie, Yusuf. (2003). Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya. PT Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-II.
Tjandrasari, Heri. (2010). Badan Penyelesaian Sengketa Kon-sumen (BPSK) dan Upaya Per-lindungan Hukum Bagi Konsumen. Masyarakat Pemantauan Per-adilan Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. www.pemantauperadilan.com. Diakses terakhir tanggal 1 April 2010.
Undang-Undang Perlindungan Konsu-men Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. (2003). Hukum tentang Perlindungan Konsumen. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003, Cetakan ketiga.
196 - Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011
PENDAHULUANSusu merupakan salah satu
bahan pangan yang sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Susu berperan sebagai asupan penting untuk kesehatan, kecerdasan, dan pertumbuhan, khususnya anak-anak.
Kesadaran masyarakat ter-hadap konsumsi susu, menjadikan susu sebagai komoditas ekonomi yang mempunyai nilai sangat strategis. Permintaan susu tumbuh sangat
cepat, yang meningkat 14,01% selama periode antara tahun 2002 dan tahun 2007. Namun, di sisi lain produksi susu Indonesia hanya tumbuh 2% (Direktorat Budidaya Ternak Ruminansia, 2010). Kesenjangan antara pertumbuhan konsumsi dengan produksi tersebut menyebabkan jumlah impor susu Indonesia terus meningkat. Bila kondisi ini tidak diwaspadai, kesenjangan tersebut dapat menyebabkan kemandirian dan kedaulatan pangan
PENGEMBANGAN SUSU SEGAR DALAM NEGERI UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN SUSU NASIONAL
Oleh : Miftah Farid1 heny Sukesi2
Naskah diterima : 27 Juni 2011Disetujui diterbitkan : 19 Desember 2011
ABSTRACTMilk is one of the important foods for fulfilling nutrition needs. There is
a wide gap between milk production and consumption. In 2002-2007, fresh milk production only grew by 2 percent; but the consumption rose by 14percent. This paper uses a descriptive analysis to explain policy and program needed by the government to develop a milk development plan. In addition, it provides material for improving coordination among government institutions. On farm level, farmers need technical assistant through government programs and Corporate Social Responsibility (CSR), facilitation grass fields, and import facilitation of cows. On marketing level, government plays a very important role in creating a captive market for spreading domestic fresh milk market, evaluating the possibility of milk processing industry to be obliged to purchase domestic fresh milk, improving capital access, and improving mutual cooperation among farmers, and among milk processing firms.
Key words: fresh milk, consumption, milk development policyJEL Classification: Q18
1 Kepala Sub Bidang Logistik pada Pusat Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta. E-mail : [email protected]
2 Kepala Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen pada Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta. E-mail : [email protected]
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011 - 197
(food soverignty) khususnya susu semakin jauh dari harapan, yang pada gilirannya berpotensi masuk dalam food trap negara eksportir. Artinya pemenuhan asupan nutrisi dari susu sangat tergantung dari kondisi pasar negara eksportir.
Disamping permintaan susu yang semakin meningkat, berbagai faktor, baik faktor eksternal maupun faktor internal, menyebabkan impor susu semakin tinggi. Dari sisi eksternal, tuntutan IMF dalam paket reformasi termasuk penghapusan kebijakan rasio atau Bukti Serap (BUSEP) yang kemudian direalisasikan melalui Inpres No 4/1998 tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional, komitmen penurunan tarif impor (GATT/WTO, FTA regional dan bilateral) secara konsisten dan berkesinambungan serta jargonisasi white revolution oleh negara-negara eksportir susu dunia, telah mendorong meningkatnya impor dan penggunaan susu bubuk oleh Industri Pengolahan Susu (IPS) (Boediyana, 2008).
Dari sisi internal, sebagaian besar (90%) produsen Susu Segar Dalam Negeri (SSDN) merupakan peternak rakyat. Kemampuan produksi mereka masih rendah, harganya relatif lebih mahal, sehingga tidak bisa bersaing dengan susu bubuk impor. Untuk meningkatkan produksinya, peternak sapi perah rakyat menghadapi berbagai permasalahan, seperti skala usaha ternak yang relatif kecil, kemampuan induk untuk memproduksi susu belum optimal, serta kemampuan penanganan ternak dan produk susu segar yang relatif rendah (Boediyana, 2008)
Secara umum, pasar susu di dalam negeri menghadapi dua permasalahan mendasar yaitu, dari sisi
hulu dan sisi hilir. Permasalahan dari sisi hulu terkait dengan rendahnya populasi sapi perah dengan tingkat produktivitas rendah (11 liter/hari), skala usaha peternak rendah (rata-rata 2-3 ekor/peternak), lahan hijau semakin terbatas, biaya impor sapi perah dan bibitnya mahal, good farming practices belum dilakukan dengan baik, permodalan kurang, dan pendampingan belum optimal (Boediyana, 2008).
Permasalahan dari sisi hilir antara lain terkait dengan rendahnya posisi tawar peternak dalam penjualan susu, tarif bea masuk produk susu rendah, harga susu internasional lebih murah, ekonomi biaya tinggi terutama dalam distribusi sapi impor dan koordinasi antar instansi pemerintah yang menangani persusuan masih kurang (Boediyana, 2008).
Permasalahan-permasalahan di atas perlu dipecahkan melalui paradigma pembangunan yang berorientasi pada pengembangan SSDN untuk memenuhi kebutuhan susu nasional. Ketergantungan yang tinggi terhadap bahan baku susu impor, sangat beresiko terhadap krisis pangan dan hiper-inflasi, apabila terjadi goncangan pasar. Pengembangan SSDN juga dapat meningkatkan kesejahteraan peternak, yang menurut Kementerian Pertanian (2010) jumlahnya 127.211 orang, serta menyediakan susu yang harganya relatif murah untuk meningkatkan konsumsi susu masyarakat.
Terkait dengan upaya meme-cahkan permasalahan di atas, maka studi ini diharapkan dapat membantu pemerintah pusat maupun daerah dalam merencanakan pembangunan persusuan yang harmonis. Di harapkan, studi ini dapat juga menyediakan bahan/materi untuk menyusun cetak biru persusuan
198 - Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011
nasional dalam rangka meningkatkan koordinasi lintas departemen dan instansi. Selain itu studi ini bertujuan untuk memberikan gambaran-gambaran kesempatan investasi bagi usaha menengah, kecil dan mikro. Metode analisis yang digunakan untuk mencapai tujuan di atas adalah dengan analisis deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui berbagai diskusi dan rapat kerja. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan, yang berupa bahan-bahan tertulis yang telah diterbitkan,
maupun dokumen-dokumen yang belum diterbitkan.
KONDISI PERSUSUAN NASIONALA. Potensi dan Produksi Susu
NasionalSalah satu unsur penting dalam
pengembangan persusuan nasional adalah pengembangan sapi perah baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Pada tahun 2005-2009 trend pertumbuhan populasi sapi perah meningkat 8,46%. Pertumbuhan populasi sapi perah bergerak lambat, bila dibandingkan dengan pertumbuhan produksi susu segar. Pada tahun 2005-2009, trend produksi susu segar hanya 5,21%.
Tabel 1 Perkembangan Populasi Sapi Perah di Indonesia per Propinsi Tahun 2005 – 2009
Keterangan : *) Angka Sementara; Sumber : Direktorat Jenderal Peternakan (2010)
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011 - 199
Dari sebaran populasi sapi perah di Indonesia, pusat populasi sapi perah adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Utara. Selama 2005 – 2009, trend pertumbuhan populasi sapi perah di Jawa Barat meningkat 5,72%, di Jawa Tengah meningkat 3,86%, di Jawa Timur meningkat 15,61%. Pada tahun 2005 populasi sapi perah di Sumatera Utara mencapai 6.521 ekor, pada tahun 2006 naik menjadi 6.526 ekor, pada tahun 2007 turun drastis menjadi 2.093 ekor, namun pada tahun 2008 naik menjadi 2.290 ekor dan 2.505 ekor pada tahun 2009 (Direktorat Ternak Budidaya Ruminansia, 2010)
Dengan melihat sebaran populasi sapi perah, pada dasarnya produksi
susu segar sudah memenuhi prinsip efisiensi3. Namun permasalahannya adalah inefisiensi di sisi kepemilikan sapi perah yang masih rendah sekitar 3-4 ekor per peternak. Walaupun Jawa Tengah pertumbuhan populasinya terendah tetapi pertumbuhan produksi susu segarnya mencapai 18% lebih tinggi dibanding pertumbuhan di Jawa Barat dan Jawa Timur yang hanya tumbuh masing-masing mencapai 4% dan 9% (Direktorat Ternak Budidaya Ruminansia, 2010). Pada tingkat nasional, produk susu Indonesia menunjukan trend yang terus meningkat secara perlahan-lahanantara tahun 205 dan 2009 (Tabel 2).
3 Prinsip efisiensi yang dimaksud adalah penyebarannya cukup merata ada disetiap pulau. Hal ini sebenarnya akan menciptakan efisiensi dalam perdagangan (disparitas harga antar wilayah kecil)
Tabel 2 Perkembangan Produksi Susu Segar di Indonesia per Propinsi Tahun 2005 – 2009
Keterangan : *) Angka SementaraSumber: Direktorat Jenderal Peternakan (2010)
200 - Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011
B. Impor SusuDalam Buku Tarif Bea Masuk
Indonesia (2007), pada dasarnya ada dua klasifikasi utama jenis susu yang dapat diimpor, yaitu: (i) susu dan kepala susu (cream) yang tidak dipekatkan maupun tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya; dan (ii) susu dan kepala susu yang dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya. Yang dimaksud dengan jenis (i) adalah: a. Dengan kandungan lemak tidak
melebihi 1% menurut beratnya (HS 0401.10.00.00).
b. Dengan kandungan lemak melebihi 1% tetapi tidak melebihi 6% menurut beratnya (HS 0401.20.00.00)
c. Dengan kandungan lemak melebihi 6% (HS 0401.30.00.00).
Sedangkan yang dimaksud dengan jenis (ii) adalah: a. Dalam bentuk bubuk, butiran atau
bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak tidak melebihi 1,5% menurut beratnya, dalam kemasan dengan berat kotor 20 kg atau lebih (HS 0402.10.90.00).
b. Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak melebihi 1,5% menurut beratnya, dalam kemasan dengan berat kotor 20 kg atau lebih (HS 0402.21.90.00).
Secara agregat, volume impor susu sebelum terjadinya krisis global (2007) selalu meningkat. Pada saat terjadinya krisis global yaitu tahun 2008, harga susu internasional meningkat tajam yang kemudian menyebabkan penurunan impor susu jenis tertentu.
Gambar 1. Volume Impor Susu Secara Agregat
Sumber: Pusat Data Perdagangan (2010)
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011 - 201
Dilihat dari neraca perdagangan selama tahun 2005 – 2009 (Tabel 3), defisit terbesar terjadi pada tahun 2007, sedangkan pada tahun 2008 dan 2009, defisit perdagangan susu semakin turun. Penurunan defisit perdagangan susu pada tahun 2008 mencapai 23%
dan pada tahun 2009 mencapai 31%. Penurunan defisit yang tinggi pada tahun 2009 disebabkan oleh penurunan impor sebesar 37%. Penurunan tersebut sangat terkait dengan harga susu dunia yang tinggi pada saat itu.
Tabel 3 Nilai Ekspor - Impor Susu dan Produk Susu hS 2
Digit (Ribu US$)
Sumber : Pusat Data Perdagangan, Kementerian Perdagangan (2010)
C. harga Susu Internasional dan Dalam Negeri
Selama kurun waktu 1999 – 2009, harga rata-rata 1,25 Butter Fat (BF) Skim Milk Powder wilayah oceania berfluktuasi dengan trend positif. Pada bulan September 2007, harga susu sebesar US$ 5225 meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan pada awal tahun 1999 sebesar US$ 1330 per ton. Hal ini diduga menyebabkan penururnan impor pada tahun 2009 (Gambar 2)
Sementara, harga susu International jenis 26% Whole Milk Powder wilayah oceania yaitu rata-rata meningkat 8 persen per tahun (Tahun 1999-2009). Dibandingkan dengan pergerakan harga 1,25 Butter Fat (BF) Skim Milk Powder, perubahan harga 26% Whole Milk Powder lebih lambat sehingga terlihat bahwa harga 26% Whole Milk Powder mengikuti pergerakan 1,25 Butter Fat (BF) Skim Milk Powder.
202 - Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011
Untuk harga di dalam negeri, khususnya di 9 (sembilan) kota/kabupaten, perkembangan harga susu selama 4 (empat) tahun (2007-2010) menunjukan kenaikan walaupun kecil. Harga rata-rata susu segar pada tahun 2010 hanya sebesar Rp 3.008,-/liter. Pada tahun 2010 kisaran harga susu segar terendah sebesar Rp 2.700,-/liter dan tertinggi sebesar Rp 3.267,-/liter.
Menurut Direktorat Pemasaran Domestik (2010), hasil analisa harga pokok penjualan susu segar (SSDN)
menunjukkan bahwa pendapatan peternak yang memilki 3 ekor sapi perah sebesar Rp 10.800,-/hari sedangkan yang memiliki 10 ekor sapi perah pendapatannya bisa mencapai Rp 219.000,-/hari. Hal ini menunjukkan perbedaan pendapatan yang mencolok sekali, karena perbedaan skala produksi. Dengan demikian, apabila rata-rata kepemilikan peternak hanya sebanyak 2 – 3 ekor, maka pendapatan peternak susu akan lebih rendah lagi.
Gambar 2. harga Susu Internasional (Oceania Area)
Sumber: www.understandingdairymarket (2010)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
US$/
ton
International 26% Whole Milk Powder Price International 1.25% BF Skim Milk Powder Price
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
Jan Feb
Mar Ap
r
Mei Jun Jul
Agus
t
Sep
Okt
Nop
Des
Jan Feb
Mar Ap
r
Mei Jun Jul
Agus
t
Sep
Okt
Nop
Des
Jan Feb
Mar Ap
r
Mei Jun Jul
Agus
t
Sep
Okt
Nop
Des
Jan Feb
Mar Ap
r
2007 2008 2009 2010
Harga Susu Bubuk
Tabel 4 Perkembangan harga Susu Sapi Segar di Sentra ProduksiDi Tingkat PeternakTahun 2007-2010 (Rp/liter)
Sumber : Direktorat Pemasaran Domestik (2010)Keterangan : - = tidak ada data
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011 - 203
Kenaikan harga susu tidak hanya terjadi di tingkat peternak, di tingkat konsumen pun harga susu bubuk dalam negeri memiliki trend yang positif. Dapat dilihat bahwa harga susu bubuk sempat mengalami kenaikan pada periode
bulan Juli 2007 hingga Desember 2008. Namun, pada tahun 2009 – 2010 harga susu bubuk cenderung stabil. Pada kurun waktu antara 2007 dan 2010, harga rata-rata susu bubuk mengalami kenaikan sebesar 30,6%.
Perkembangan harga susu kental manis juga memiliki trend yang positif artinya mengalami kenaikan pada periode tahun 2008 - 2009. Harga
rata-rata susu kental manis mengalami kenaikan per tahun sebesar 6,9% pada periode tahun 2008 – 2010.
Gambar 4. Perkembangan harga Susu Kental Manis (dalam Rp/395 gr)
Sumber: Badan Pusat Statistik (2010)
6.200
6.400
6.600
6.800
7.000
7.200
7.400
7.600
7.800
Jan Feb
Mar
Apr
Mei
Jun Jul
Agus
t
Sep
Okt
Nop
Des
Jan Feb
Mar
Apr
Mei
Jun Jul
Agus
t
Sep
Okt
Nop
Des
Jan Feb
Mar
Apr
2008 2009 2010
Harga Susu Kental Manis
Gambar 3. Perkembangan harga Susu Bubuk Dalam Negeri (dalam Rp/400 gr)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
US$/
ton
International 26% Whole Milk Powder Price International 1.25% BF Skim Milk Powder Price
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
Jan Feb
Mar
Apr
Mei
Jun Jul
Agus
t
Sep
Okt
Nop
Des
Jan Feb
Mar
Apr
Mei
Jun Jul
Agus
t
Sep
Okt
Nop
Des
Jan Feb
Mar
Apr
Mei
Jun Jul
Agus
t
Sep
Okt
Nop
Des
Jan Feb
Mar
Apr
2007 2008 2009 2010
Harga Susu Bubuk
Sumber: Ditjen Perdagangan Dalam Negeri (2010)
204 - Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011
KEBIjAKAN PERSUSUAN NASIONALBeberapa kebijakan yang terkait
dengan pengembangan persusuan nasional dan implementasinya masih perlu dioptimalkan. Antara lain adalah:
a. Undang-undang N0.18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan hewan, dalam pasal-pasal antara lain menyebutkan :1) Pasal 35, mengamanatkan
pemerintah pusat dan peme-rintah daerah agar memfasilitasi pengembangan unit pasca panen produk hewan berskala kecil dan menengah.
2) Pasal 37, menyatakan pemerintah membina terselenggaranya kemitraan yang sehat antara industri pengolahan dan peternak dan/atau koperasi yang menghasilkan produk hewan yang digunakan sebagai bahan baku industri.
3) Pasal 59, menyatakan bahwa untuk memasukkan produk hewan ke Indonesia wajib memperoleh izin pemasukan dari menteri terkait di bidang perdagangan setelah memperoleh rekomendasi: untuk produk hewan segar dari menteri dan produk hewan olahan dari pimpinan instansi yang bertanggung jawab di bidang pengawasan obat dan makanan dan/atau menteri.
4) Pasal 60, pemerintah daerah memberikan nomor kontrol veteriner dan melakukan pembinaan, sedangkan pada pasal 62. pemerintah daerah wajib memiliki rumah potong hewan yang memenuhi persyaratan teknis.
b. Peraturan Presiden RI N0 62 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu.
Industri dan usaha yang mendapat fasilitas pajak penghasilan dalam penenaman modal, antara lain:1) Kelompok industri susu dan
makanan dari susu (susu bubuk, susu kental manis, susu UHT, susu pasteurisasi)
2) Usaha peternakan besar/kecil (sapi potong, sapi perah)
c. Peraturan Presiden RI N0 28 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Industri Nasional
Pada pasal 2 disebutkan bahwa menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian menyusun dan menetapkan peta panduan (Road Map) pengembangan klaster industri prioritas antara lain industri berbasis agro (industri susu),
Lampiran PP No. 28 tersebut, menyebutkan dalam strategi pembangunan industri nasional : penguatan, pendalaman dan penumbuhan enam klaster industri prioritas yang kelompok industri agro adalah industri pengolahan susu.
d. Peraturan Menteri Keuangan No. 131/PMK.05/2009 Tentang Kredit Usaha Pembibitan Sapi dan Peraturan Menteri Pertanian No. 40/Permentan/PD-400/9/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan kredit Usaha Pembibitan Sapi
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011 - 205
Peraturan di atas diber-lakukan untuk menciptakan tatanan iklim usaha yang mampu mendorong pelaku usaha untuk bergerak dibidang pembibitan sapi melalui penyediaan skim Kredit Kredit Usaha Pembibitan sapi (KUPS) dengan suku bunga bersubsidi. Tujuan dari KUPS adalah untuk meningkatkan populasi induk sapi potong dan sapi perah. Plafon kredit per pelaku usaha paling banyak sebesar Rp. 66.315.000.000,- dengan suku bunga 5% / tahun jangka waktu maximum 6 tahun.
Suku bunga yang hanya 5%/tahun ternyata belum bisa menarik minat peternak untuk memanfaatkan skim kredit tersebut. Beberapa kesulitan yang dihadapi antara lain: (1) Usaha pembibitan memerlukan grace periode dan turn over yang cukup lama (nimimal satu tahun), sehingga dengan suku bunga modal 5%/tahun masih belum bisa tertutupi oleh nilai IRR (internal rate of return); (2) Salah satu syarat perusahaan peternakan yang akan memanfaatkan skim kredit KUPS, adalah harus bermitra dan membina peternak rakyat melalui sistem gaduh; (3) Peternak rakyat yang ingin memanfaatkan skim kredit KUPS, seringkali terbentur pada masalah persyaratan yang diminta pihak Bank peserta KUPS
seperti syarat agunan (anvalis), laporan usaha dan sebagainya.
e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
Berdasarkan kebijakan di atas, investasi di industri pengolahan susu bubuk dan susu kental manis bersifat terbuka dengan syarat kemitraan. Dengan kebijakan tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia melalui peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil yang disertai dengan kemitraan.
f. Kebijakan Tarif Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai
Berdasarkan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia tahun 2007 yang diterbitkan Kementerian Keuangan, impor bibit dan sapi tarif bea masuknya 0%, impor susu dan produk susu bea masuknya 5% kecuali impor yoghurt bea masuknya 10%.
206 - Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011
PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN SSDN
Pada dasarnya peluang pasar dalam negaeri persusuan nasional cukup besar, namun peluang tersebut dapat terabaikan jika tantangan-tantangan
eksternal program pengembangan SSDN tidak dapat dijawab. Oleh karena itu memetakan peluang dan tantangan merupakan tahapan penting dalam menyusun strategi pengembangan persusuan nasional.
Sumber: Kementerian Keuangan (2007)
Tabel 5 Tarif Bea Masuk Ternak dan hasil Ternak Sapi
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011 - 207
Peluang yang dapat dioptimal-kan untuk pengembangan sub sektor industri susu nasional antara lain:1. Permintaan/kebutuhan susu segar
maupun produk turunannya diper-kirakan terus meningkat seiring dengan pertambahan populasi, pertumbuhan ekonomi, perbaikan tingkat pendidikan, kesadaran gizi dan perubahan gaya hidup.
2. Asumsi pertumbuhan ekonomi 6,1%, konsumsi susu /kapita/th akan meningkat 10,75 kg sehingga kebutuhan susu dalam negeri meningkat > 2 juta ton. Indonesia kekurangan susu sekitar 72% (Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia).
3. Program menggalakan konsumsi susu segar atau susu pasturisasi, sterilisasi (UHT) langsung (tanpa perlakuan dengan teknologi tinggi) ke konsumen (anak usia sekolah, karyawan industri, PNS, ABRI).
4. Berkembangnya agroindustri susu olahan di Indonesia.
5. Tataniaga komoditi susu lebih terbuka/pasar bebas.
Sedangkan tantangan yang harus dijawab dalam pengembangan persusuan nasional antara lain:1. Harga bahan baku susu impor untuk
jenis tertentu relatif murah.2. Kesepakatan kawasan perdagangan
bebas RRT-AFTA.3. Investor asing terbatas pada IPS
yang berskala besar.4. Kompetisi penggunaan lahan untuk
hijauan pakan ternak.5. Pakan konsentrat relatif mahal.6. Pasar SSDN yaitu industri peng-
olahan susu (IPS) hanya dikuasi oleh perusahaan besar sehingga ada kecenderungan bersifat oligopsoni.
KEBIJAKAN PENINGKATAN PER-SUSUAN NASIONAL
A. Kondisi Yang DiharapkanPengembangan persusuan
nasional terutama ditujukan untuk mengurangi ketergantungan ter-hadap bahan baku susu impor serta meningkatkan konsumsi susu masyarakat. Impor bahan baku susu secara gradual dikurangi dan disubstitusi dengan bahan baku SSDN. Peningkatan produksi SSDN dilakukan melalui penambahan populasi sapi perah serta meningkatkan produktivitas susu.
Target yang diharapkan pada tahun 2014, populasi sapi perah meningkat dari 423.891 ekor pada tahun 2010, menjadi 613.554 ekor pada tahun 2014 atau meningkat sebesar 44,74%. Disamping itu produksi susu juga diharapkan meningkat dari 727.539 ton pada tahun 2010 menjadi 1.297.034 ton pada tahun 2014, atau terjadi peningkatan produktivitas susu 23,17% selama kurun waktu 4 tahun (Kementerian Pertanian, 2010).
Konsumsi susu masyarakat saat ini baru mencapai 10,47 kg/kapita/tahun. Dengan adanya peningkatan produksi SSDN, akses masyarakat untuk mengkonsumsi susu meningkat, baik dari segi harga yang relatif lebih murah maupun dari kualitas susu yang lebih baik. Pada tahun 2014, konsumsi susu per kapita meningkat menjadi sekitar 15 kg/kapita/tahun, dimana 40 persen dipenuhi dari SSDN (www.livestockreview.com).
Untuk mencapai target pada tahun 2014 tersebut, perlu disusun strategi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam persusuan nasional. Pemangku
208 - Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011
kepentingan yang terlibat mulai dari penyedia sarana produksi peternakan sapi perah (hulu), peternak sapi perah (on farm), penanganan susu segar (pasca panen), sampai pemasaran (marketing), serta lembaga pendukung yang diperlukan (kebijakan pemerintah, lembaga keuangan, petugas penyuluh lapang, koperasi susu dan sebagainya).
B. Strategi Pengembangan Per-susuan Nasional
1. Peningkatan Populasi Sapi PerahPeningkatan populasi sapi
perah betina induk mutlak diperlukan agar produksi SSDN bisa meningkat. Penambahan populasi sapi perah dapat berasal dari kelahiran dan impor. Permasalahan yang sedang dihadapi terkait dengan penambahan sapi perah dari kelahiran adalah skala usaha sapi perah yang masih kecil, dan tidak jarang pada saat-saat membutuhkan dana, peternak sering menjual sapinya. Permasalahan dalam penambahan sapi perah dari impor adalah tingginya biaya distribusi dari pelabuhan ke sentra peternakan sapi perah. Besarnya penambahan populasi sapi dari kelahiran tergatung dari umur beranak pertama, calving interval (CI, jarak antar beranak satu dengan berikutnya), calving size (jumlah anak sapi per kelahiran), dan mortalitas (tingkat kematian, terutama anak sapi).
2. Fasilitasi Kebutuhan Lahan Upaya pengembangan sapi
perah, lahan untuk hijauan pakan ternak mutlak diperlukan. Kebutuhan lahan untuk makanan ternak sulit dipenuhi oleh peternak rakyat, karena lahan yang dimiliki peternak relatif sempit dan diutamakan untuk tanaman pangan.
Pemerintah daerah diharapkan dapat membantu melalui pemanfaatan lahan kosong untuk tanaman makanan ternak, baik lahan kosong milik perhutani, PTPN atau yang dikelola pemerintah daerah. Hijauan makanan ternak hasil budidaya memiliki kualitas nutrisi yang lebih baik dibandingkan dengan rumput lapang atau limbah pertanian, sehingga dapat meningkatkan produktivitas susu.
3. Kemudahan Investasi Industri
PersusuanPengembangan industri
persusuan berbasis SSDN untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, memerlukan dukungan investasi pada seluruh sistem, mulai dari hulu hingga hilir. Pentingnya dukungan investasi pada sistem hulu-hilir karena produksi susu segar di tingkat on farm memerlukan input yang dihasilkan industri lain, seperti industri pakan, obat-obatan dan semen untuk Inseminasi Buatan (IB). Susu segar yang dihasilkan peternak juga memerlukan IPS untuk menampung dan mengolah lebih lanjut agar menjadi produk yang mempunyai nilai tambah, awet, mudah didistribusikan dan siap konsumsi.
4. Pengembangan Kemampuan
PeternakAplikasi good farming practices
oleh peternak dapat mengoptimalkan produktivitas dan kualitas susu segar yang dihasilkan peternak. Penyebab kurang berkembangnya peternakan sapi perah rakyat yang terjadi selama ini, antara lain karena rendahnya produksi dan kualitas susu segar yang dihasilkan. Menurut Pambudy (2009), rendahnya kualitas susu dapat menurunkan harga jual. Susu segar dengan kandungan bakteri (TPC) diatas 3.000.000/cc,
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011 - 209
harganya bisa sampai Rp 2.750,- per liter, sementara biaya memproduksi susu berkisar antara Rp 2.500,- sampai Rp 3.000,- per liter.
Good farming practices mencakup manajemen pemeliharaan selama periode rearing, tata cara perkawinan, pemeliharaan sapi kering, pemberian pakan, penanganan kesehatan induk penanganan susu segar. Praktik-praktik tersebut jika dilakukan dengan baik dapat mengoptimalkan jumlah kelahiran dan jumlah periode laktasi selama hidup induk sapi, yang selanjutnya dapat meningkatkan produksi susu (dan anak) yang dihasilkan.
5. Fasilitasi Kebutuhan Modal Diantara pelaku agribisnis
persusuan, kelompok yang paling lemah modal adalah penghasil SSDN dimana 90% merupakan peternak rakyat. Peternak rakyat dengan modal terbatas, pada umumnya tidak mampu menyediakan pakan yang optimal yang diperlukan sapi. Peternak hanya memberi pakan seadanya, seperti rumput lapang, limbah pertanian serta pengganti konsentrat (dedak, limbah pabrik dan sebagainya). Akibatnya produktivitas sapi rendah.
Pemberian modal murah bagi peternak, dapat meningkatkan kemampuan peternak untuk pengadaan input produksi berkualitas, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produksi SSDN. Modal tidak hanya berdampak pada produktivitas sapi, tetapi juga pada peningkatan populasi.
6. Meningkatkan Serapan Susu Segar Peningkatan daya serap SSDN
dengan harga yang menguntungkan peternak, dapat membantu peternak
untuk mengembangkan usahanya. Peningkatan serapan susu segar dapat dilakukan melalui program minum susu bagi anak-anak usia sekolah (school milk).
Di Indonesia program school milk, juga telah dilaksanakan di beberapa daerah. Pemerintah Daerah Sukabumi, mencanangkan Program Gerimis Bagus (Gerakan Minum Susu bagi Anak Usia Sekolah), untuk meningkatkan konsumsi susu segar di kalangan murid SD, dengan dana dari APBD. Pemerintah daerah lainnya, seperti Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan dan Semarang, Jawa Tengah juga telah merintis program school milk (http://repository.ipb.ac.id)
7. Mengembangkan Kemitraan Yang Sehat
Ketergantungan peternak ter-hadap IPS dalam memasarkan pro-duknya seringkali menciptakan perilaku monopsoni. Selama ini peternak hanya sebagai price taker yang ditetapkan oleh pihak IPS. Standar harga dasar (floor price) seperti pada komoditas beras/padi, belum diterapkan pada komoditas susu. Bahkan ketika harga bahan baku susu dunia naik, harga beli SSDN oleh IPS relatif tetap, namun bila harga bahan baku di pasar dunia turun, harga beli SSDN oleh IPS ikut turun. Hal ini diperkuat oleh semakin lebarnya disparitas harga susu di tingkat konsumen dengan harga beli IPS di tingkat peternak.
8. Memperkuat Pasar Susu Domestik Kerjasama regional RRT-
ASEAN FTA dan AANZ-FTA, merupakan tantangan bagi industri persusuan nasional untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas SSDN. Ketergantungan yang tinggi terhadap
210 - Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011
bahan baku, dapat mengancam kedaulatan susu nasional. Isu-isu negatif dunia seperti bencana alam, dan wabah penyakit, akan berdampak pada permintaan susu nasional. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk memperkuat pasar dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan susu nasional dari SSDN.
Diperlukan koordinasi yang saling mendukung antara peternak, konsumen dan pemerintah, agar kedaulatan susu nasional dapat tercapai. Peternak perlu ditingkatkan kemampuan managementnya untuk menghasilkan susu berkualitas yang diikuti dengan produktivitas yang tinggi. Upaya ini akan meningkatkan daya
saing SSDN terhadap bahan baku susu impor, dan jaminan keamanan bagi yang mengkonsumsi susu segar.
Keterlibatan Pemerintah dalam memperkuat pasar susu domestik sangat penting, melalui pembinaan terhadap peternak, kampanye terhadap konsumen serta pengawasan terhadap kualitas susu cair siap konsumsi. Industri pengolahan susu yang mengemas susu cair perlu mencantumkan bahan baku susu tersebut dengan jelas, apakah dari susu bubuk impor, SSDN atau campuran. Transparansi tentang bahan baku yang digunakan dapat menjadi informasi bagi konsumen yang telah paham kualitas susu murni, dalam memutuskan susu yang akan dikonsumi.
Gambar 5. Contoh Mekanisme School milk
Sumber: Kementerian Pendidikan Nasional (2010)
Gambar 5. Contoh Mekanisme School milk
Sumber: Kementerian Pendidikan Nasional (2010)
Gambar 6. Penguatan Pasar Susu Segar Dalam Negeri*
Catatan: * Hasil analisis
Pemerintah Daerah
Sumber dana: - APBD - BOS - Dinas Kesehatan - Dinas Peternakan - CSR, dll
Peternak sapi perah
Koperasi/kelompok peternak
Susu segar murah
dan berkua
litas
Kesehatan dan
kecerdasan generasi
muda
daya serap SSDN dan
kesejahteraan peternak Penyalur
Harga dan jumlah disalurkan infrastruktur
Anak sekolah
PEMERINTAH
PERBAIKAN MANAJEMEN BETERNAK
KELOMPOK PETERNAK
SAPI PERAH
SUSU SEGAR BERKUALITAS
IPS PASTEURISASI
UHT FERMENTASI
ICE CREAM, DLL
PENAWARAN
PASAR PRODUK
SUSU BERKUALITAS
BERBASIS SSDN
PERMINTAAN K
ON
SU
MEN
PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN
KAMPANYE DAN PEMAHAMAN SUSU MURNI
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011 - 211
C. Optimalisasi dan Revisi Kebijakan Pengembangan Persusuan Nasio-nal
Pengembangan industri per-susuan dalam negeri, selain untuk mengurangi ketergantungan terhadap susu impor, juga mendukung program swasembada daging tahun 2014 yang dicanangkan dalam Program Revitalisasi Pertanian Perikanan dan Kehutanan (RPPK) tahun 2005. Dalam pelaksanaannya, pengembangan industri persusuan, tidak dapat hanya dilakukan
oleh satu kementrian atau instansi. Keberhasilannya sangat ditentukan oleh kontribusi dari kementerian dan instansi terkait lainnya.
Konstribusi dari masing-masing instansi dan kementrian diterjemahkan melalui kebijakan, terutama kebijakan berupa insentif bagi tumbuh-kembangnya produksi SSDN serta kebijakan penguatan pasar dalam negeri. Secara umum kebijakan dan insentif yang sudah ada dapat dilihat pada Tabel 6.
Gambar 5. Contoh Mekanisme School milk
Sumber: Kementerian Pendidikan Nasional (2010)
Gambar 6. Penguatan Pasar Susu Segar Dalam Negeri*
Catatan: * Hasil analisis
Pemerintah Daerah
Sumber dana: - APBD - BOS - Dinas Kesehatan - Dinas Peternakan - CSR, dll
Peternak sapi perah
Koperasi/kelompok peternak
Susu segar murah
dan berkua
litas
Kesehatan dan
kecerdasan generasi
muda
daya serap SSDN dan
kesejahteraan peternak Penyalur
Harga dan jumlah disalurkan infrastruktur
Anak sekolah
PEMERINTAH
PERBAIKAN MANAJEMEN BETERNAK
KELOMPOK PETERNAK
SAPI PERAH
SUSU SEGAR BERKUALITAS
IPS PASTEURISASI
UHT FERMENTASI
ICE CREAM, DLL
PENAWARAN
PASAR PRODUK
SUSU BERKUALITAS
BERBASIS SSDN
PERMINTAAN K
ON
SUM
EN PEMBINAAN DAN
PENDAMPINGAN
KAMPANYE DAN PEMAHAMAN SUSU MURNI
Gambar 6. Penguatan Pasar Susu Segar Dalam Negeri*
Catatan: * Hasil analisis
Tabel 6 Kebijakan Terkait Dengan Pengembangan Industri Persusuan
Kebijakan Materi Instansi/ Lembaga terlibat
- PP No. 44 Tahun 1997; Keppres No. 99 Tahun 1998;
- SK Mentan No. 940 Tahun 1997;
- SK Mentan No. 944 Tahun 1997
Kewajiban pengusaha besar dan menengah untuk bermitra dengan pengusaha kecil, pedoman bermitra dan Penetapan Tingkat Hubungan Kemitraan Usaha Pertanian
Kementan, Kemenperind; Kemenkop dan UMKM
PP No.6/2007 tentang pengembangkan silvopastura
Pemanfaatan kawasan hutan sebagai sumber pakan ternak
Kementan, Kemenhut
UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Hak guna usaha (HGU) diberikan dalam satuan yang luas dan jangka waktu yang panjang (sampai 95 tahun).
Kementan, Badan Pertanahan; Nasional, Kemen BUMN;
PP No 111 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas PP No 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
Investasi di industri pengolahan susu bubuk dan susu kental manis bersifat terbuka dengan syarat kemitraan.
Kemenperind; BKPM Kemenkop dan UMKM
Permenkeu No. 131/PMK/05/2009 tentang KUPS
Subsidi bunga untuk pembibitan sapi. Peternak membayar bunga pinjaman bank sebesar 5%.
Kementan, Kemenkeu
Permentan No 40/Permentan/PD.400/9/2009 tentang pedoman pelaksanaan KUPS
Persyaratan pengajuan KUPS bagi kelompok peternak dan perusahaan
Kemenkeu; Kementan;
UU No18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- Kemudahan pemasukan sapi bibit impor untuk meningkatkan mutu dan keragaman genetik, serta mengatasi kekurangan bibit di dalam negeri
- Dukungan terhadap daerah untuk melakukan kerjasama antara pengusaha peternakan dan pengusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber pakan ternak murah.
- Peruntukan lahan untuk peternakan - Larangan pemotongan betina produktif - Pemerintah agar memfasilitasi pengembangan
unit pasca panen produk hewan berskala kecil dan menengah.
- Kemitraan yang sehat antara industri pengolahan dan peternak dan/atau koperasi yang menghasilkan produk hewan yang digunakan sebagai bahan baku industri
Kementan; PEMDA; Kemenperind; Kemenkop dan UMKM Kemendag
212 - Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011
Sebagian besar kebijakan yang telah ada, masih berorientasi pada produsen, dalam hal ini sub sistem on farm. Bahkan beberapa kebijakan dinilai kurang operasional. Sehingga masih diperlukan revisi kebijakan maupun instrumen tambahan
untuk mengoperasionalkan kebijakan tersebut, serta kebijakan tambahan untuk meningkatkan konsumsi SSDN. Beberapa kebijakan yang perlu ditambahkan seperti ditampilkan pada Tabel 7.
Kebijakan Materi Instansi/ Lembaga terlibat
- PP No. 44 Tahun 1997; Keppres No. 99 Tahun 1998;
- SK Mentan No. 940 Tahun 1997;
- SK Mentan No. 944 Tahun 1997
Kewajiban pengusaha besar dan menengah untuk bermitra dengan pengusaha kecil, pedoman bermitra dan Penetapan Tingkat Hubungan Kemitraan Usaha Pertanian
Kementan, Kemenperind; Kemenkop dan UMKM
PP No.6/2007 tentang pengembangkan silvopastura
Pemanfaatan kawasan hutan sebagai sumber pakan ternak
Kementan, Kemenhut
UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Hak guna usaha (HGU) diberikan dalam satuan yang luas dan jangka waktu yang panjang (sampai 95 tahun).
Kementan, Badan Pertanahan; Nasional, Kemen BUMN;
PP No 111 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas PP No 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
Investasi di industri pengolahan susu bubuk dan susu kental manis bersifat terbuka dengan syarat kemitraan.
Kemenperind; BKPM Kemenkop dan UMKM
Permenkeu No. 131/PMK/05/2009 tentang KUPS
Subsidi bunga untuk pembibitan sapi. Peternak membayar bunga pinjaman bank sebesar 5%.
Kementan, Kemenkeu
Permentan No 40/Permentan/PD.400/9/2009 tentang pedoman pelaksanaan KUPS
Persyaratan pengajuan KUPS bagi kelompok peternak dan perusahaan
Kemenkeu; Kementan;
UU No18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- Kemudahan pemasukan sapi bibit impor untuk meningkatkan mutu dan keragaman genetik, serta mengatasi kekurangan bibit di dalam negeri
- Dukungan terhadap daerah untuk melakukan kerjasama antara pengusaha peternakan dan pengusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber pakan ternak murah.
- Peruntukan lahan untuk peternakan - Larangan pemotongan betina produktif - Pemerintah agar memfasilitasi pengembangan
unit pasca panen produk hewan berskala kecil dan menengah.
- Kemitraan yang sehat antara industri pengolahan dan peternak dan/atau koperasi yang menghasilkan produk hewan yang digunakan sebagai bahan baku industri
Kementan; PEMDA; Kemenperind; Kemenkop dan UMKM Kemendag
Kebijakan Materi Instansi/ Lembaga terlibat
- PP No. 44 Tahun 1997; Keppres No. 99 Tahun 1998;
- SK Mentan No. 940 Tahun 1997;
- SK Mentan No. 944 Tahun 1997
Kewajiban pengusaha besar dan menengah untuk bermitra dengan pengusaha kecil, pedoman bermitra dan Penetapan Tingkat Hubungan Kemitraan Usaha Pertanian
Kementan, Kemenperind; Kemenkop dan UMKM
PP No.6/2007 tentang pengembangkan silvopastura
Pemanfaatan kawasan hutan sebagai sumber pakan ternak
Kementan, Kemenhut
UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Hak guna usaha (HGU) diberikan dalam satuan yang luas dan jangka waktu yang panjang (sampai 95 tahun).
Kementan, Badan Pertanahan; Nasional, Kemen BUMN;
PP No 111 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas PP No 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
Investasi di industri pengolahan susu bubuk dan susu kental manis bersifat terbuka dengan syarat kemitraan.
Kemenperind; BKPM Kemenkop dan UMKM
Permenkeu No. 131/PMK/05/2009 tentang KUPS
Subsidi bunga untuk pembibitan sapi. Peternak membayar bunga pinjaman bank sebesar 5%.
Kementan, Kemenkeu
Permentan No 40/Permentan/PD.400/9/2009 tentang pedoman pelaksanaan KUPS
Persyaratan pengajuan KUPS bagi kelompok peternak dan perusahaan
Kemenkeu; Kementan;
UU No18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- Kemudahan pemasukan sapi bibit impor untuk meningkatkan mutu dan keragaman genetik, serta mengatasi kekurangan bibit di dalam negeri
- Dukungan terhadap daerah untuk melakukan kerjasama antara pengusaha peternakan dan pengusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber pakan ternak murah.
- Peruntukan lahan untuk peternakan - Larangan pemotongan betina produktif - Pemerintah agar memfasilitasi pengembangan
unit pasca panen produk hewan berskala kecil dan menengah.
- Kemitraan yang sehat antara industri pengolahan dan peternak dan/atau koperasi yang menghasilkan produk hewan yang digunakan sebagai bahan baku industri
Kementan; PEMDA; Kemenperind; Kemenkop dan UMKM Kemendag
Catatan: KUPS: Kredit Usaha Pembibitan Sapi
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011 - 213
Tabel 7 Kebijakan Yang Masih Perlu Direvisi Atau DitambahkanKebijakan Instansi/ Lembaga
terlibat Kebijakan yang perlu direvisi Permenkeu No. 131/PMK/05/2009, tentang KUPS untuk pembibitan sapi suku bunga 5% dinilai masih terlalu tinggi, karena perusahaan wajib membina peternak rakyat. Perlu ada kajian suku bunga KUPS yang layak
Kementan; Kemenkeu; Perbankan
Keppres No.4/1998 tentang tidak berlakunya Keppres No.2/1985, Bahwa IPS tidak diwajibkan menyerap SSDN. Kebijakan ini perlu ditinjau ulang, mengingat peternak sangat tergantung pada IPS sebagai pasar SSDN
Kementan; Kemendag; Kemenperind.
Kebijakan yang perlu ditambahkan Pengalihan impor sapi bakalan menjadi sapi induk (betina) Kementan; Kemendag
Kebijakan impor calon bibit (pedet) Kementan; Kemendag Fasilitasi pabrik pakan berbahan baku lokal dan prioritas pasar dalam negeri bagi produsen bahan baku pakan (bungkil kelapa sawit; tetes dsb)
Kementan, Menperind; Kemen BUMN; Kemendag
Penetapan harga dasar/harga pokok produksi SSDN Kementan; Kemenkeu; Kemendag
Ketersediaan dan kepastian hukum dalam pengembangan kawasan peternakan sapi perah terintegrasi pola cluster
Kementan, Pemprov/Pemda
Kebijakan pendorong tumbuhnya industri pengolahan SSDN (IPS) skala kecil menengah
Kemenkeu; Menperind; Kemenkop dan UMKM
Kebijakan pengurangan pajak impor mesin dan peralatan industri hilir yang belum bisa disediakan oleh industri dalam negeri (cooling unit, mesin pasteurisasi, mesin packaging, mesin perah, cool storage)
Kemenkeu; Kemendag; Kemenperind
Kebijakan peningkatan pajak impor untuk produk hilir yang sudah mampu diproduksi di dalam negeri
Kemenkeu; Kemendag; Kemenperind
Kebijakan pengembangan dana riset untuk pengembangan industri persusuan dengan pendekatan hulu hilir secara komprehensif sampai pada tahap komersialisasi teknologinya.
Kementan; Kemendiknas; Kemen Riset dan Teknologi
Kebijakan pengembangan dana riset untuk memperkuat posisi tawar SSDN dan produk olahannya
Kementan; Kemendiknas; Kemen Riset dan Teknologi
Pengembangan skema pengusahaan lahan kepada petani produktif dari lahan HGU yang habis masa perijinannya
Kementan; BPN; Kemen. BUMN
Memperbesar/memperluas jangkauan KUPS
Kemenkeu
Bantuan sarana produksi peternakan sapi perah (kandang; peralatan perah) untuk peningkatan produksi dan produktivitas
Kementan
Bantuan untuk rakyat miskin atau bencana dalam bentuk pangan berbahan baku SSDN
Kemenkesra; Bulog
Pelatihan penerapan SJMKP untuk peningkatan kualitas SSDN Kementan; Kemenperind; Kemenkop dan UMKM
Kebijakan promosi minum susu segar, utamanya bagi anak usia pertumbuhan melalui program milk schooling.
Pemprov/Pemkab; Kemendiknas; Kemenkes; Kementan
Mendorong sistem identifikasi sapi perah Indonesia (SISI) untuk peningkatan kualitas bibit (upgrading)
Pemprov/Pemkab; Kementan
Penanganan penyakit brucelosis dan mastitis serta good farming practices Pemprov/Pemkab; Kementan
214 - Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011
Pembangunan SSDN menuntut keterpaduan hulu dan hilir, terencana, tepat dan berkesinambungan. Keber-hasilan dalam satu rantai, tidak akan berhasil bila tidak ada kesinambungan antara rantai sebelumnya dan rantai sesudahnya. Pemenggalan kewena-ngan lintas kementerian menyulitkan koordinasi strategi, kebijakan dan program pengembangan SSDN. Oleh karena itu, revisi PP 17/1986 tentang kewenangan, pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri seyogianya diarahkan untuk menjadikan industri persusuan menjadi satu dalam Kementerian Pertanian.
Selain koordinasi dan keter-paduan antar Instansi Pemerintah (G), keberhasilan program juga ditentukan oleh peran aktif dunia bisnis/B (penggerak, penghela dan pelaksana utama) dan akademisi (A) sebagai penghasil teknologi termasuk pemikiran ilmiah pengembangan SSDN. Peran aktif harus terencana, terpadu dan terprogram sehingga terjadi keserasian yang saling terkait dan menguatkan.
PROGRAM PENGEMBANGAN PER-SUSUAN NASIONAL
1. Program UtamaProgram utama dirumuskan
melalui diskusi dengan stakeholder persusuan nasional. Program utama merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk pengembangan persusuan nasional. Industri persusuan merupakan suatu sistem yang terintegrasi dari hulu sampai hilir, sehingga program yang dilakukan harus secara holistik, tidak bisa parsial.
a. Impor Induk Sapi dan Pengem-bangan Kemampuan Peternak
Sapi yang diimpor adalah sapi induk muda yang sedang bunting pertama kali, usia antara 3-5 bulan kebuntingan. Hal yang perlu dihindari adalah impor sapi bunting yang berumur diatas 6 tahun. Sapai induk yang telah berumur diatas 6 tahun kemungkinan besar tidak akan dapat lagi bunting. Impor sapi dara yang belum bunting juga berpeluang sapi majir.
Program impor induk produktif dilakukan secara bertahap, sambil menyiapkan sumberdaya peternak dan sumberdaya pendukungnya. Rencana impor induk sapi dan target pemenuhan komsumsi susu dalam negeri dari SSDN ditampilkan pada tabel 8.
Sumber: Bahan Presentasi. IPB. Bogor, Tim Satgas PSDS IPB, 2010. Road Map Skenario PSDS (Program Swasembada Daging Sapi) 2014.
Tabel 8 Perencanaan Impor Induk Sapi Perah dan Produksi SSDN
Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 Impor induk produktif (000 ekor) 5 20 20 20 20 Populasi induk bibit (000 ekor) 45,0 55,5 74,5 91,0 118,8 Kebutuhan susu (000 ton) 2.206,2 2.231,6 2.257,1 2.283,1 2.309,2
SSDN (000 ton) 661,8 714,1 767,4 821,9 982,0 30 32 34 36 43
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011 - 215
b. Fasilitas Kredit dan Pendampingan Industri Pakan Skala Kecil
Harga pakan masih relatif memberatkan peternak. Harga pakan ternak tinggi, karena ketergantungan bahan baku impor, sementara subsidi mulai dihilangkan. Pakan konsentrat dengan memanfaatkan bahan baku lokal yang murah bisa diproduksi di lokasi sentra peternakan sapi perah. Komposisi pakan fleksibel disesuaikan dengan kelimpahan bahan baku, sehingga ketergantungan terhadap bahan baku import bisa semakin dikurangi.
Industri pakan ternak skala kecil (mini feed mill) biasanya dikelola oleh koperasi atau kelompok peternak dengan fasilitas kredit bersubsidi dari pemerintah. Dalam konteks ini bahan pakan dapat berupa: 1) hasil sisa tanaman (crop residues); 2) hasil ikutan/ samping/limbah tanaman (crop-by products); dan 3) hasil ikutan/samping/limbah industri agro (Sukria dan Krisnan, 2009). Untuk menjamin ketersediaan bahan baku pakan, pemerintah perlu melakukan restrukturisasi tataniaga bahan baku lokal. Sebagai contoh, bungkil kelapa sawit yang selama ini di ekspor, diprioritaskan untuk dipasarkan di dalam negeri sebagai bahan baku pakan.
Lembaga yang melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap industri pakan skala kecil perlu dibentuk, untuk menjamin kualitas produk pakan yang dihasilkan. Dalam membeli pakan, peternak serungkali hanya mempertimbangkan harga yang murah, tanpa melihat kualitas. Beberapa pabrik pakan tidak mencantumkan kandungan nutrisi, sehingga peternak seringkali tidak mengetahui kandungan nutrisinya.
c. Optimalisasi Pemanfaatan Skim Kredit Peternakan
Salah satu program pemerintah untuk meningkatkan populasi induk sapi adalah melalui pemberian kredit bersubsidi dengan bunga 5%/th kepada peternak pembibitan sapi. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 131/PMK.05/2009. Skim kredit KUPS bisa diakses oleh peternak sapi perah untuk meningkatkan skala usahanya.
Skim Kredit KUPS tidak hanya dapat diakses langsung oleh peternak sapi perah. Salah satu pelaku usaha yang menurut Pedoman Pelaksanaan KUPS Kementerian Pertanian (2009) dapat memanfaatkan KUPS adalah Koperasi. Koperasi dapat bertindak sebagai anvalis (lembaga penjamin) bagi peternak anggotanya yang ingin memanfaatkan KUPS. Peran koperasi sebagai anvalis bukan hal baru, karena pada skim kredit sebelumnya, koperasi selalu bertindak sebagai penyalur kredit dari pemerintah kepada peternak. Peternak menerima kredit KUPS dalam bentuk induk sapi bunting yang disediakan oleh koperasi, selanjutnya peternak membayar cicilan kredit kepada koperasi dengan susu segar yang dihasilkan setiap hari, selama masa laktasi.
Pengadaan induk bunting melalui kredit KUPS adalah induk bunting impor dan lokal. Untuk memudahkan impor, beberapa koperasi berkolaborasi. Dengan cara itu, biaya transportasinya akan menjadi lebih murah. Biaya transportasi impor induk akan semakin mahal bila jumlahnya kurang dari 2000 ekor, karena menggunakan angkutan pesawat. Dalam jumlah besar, transportasi bisa dilakukan menggunakan kapal laut yang biayanya relatif murah.
216 - Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011
Agar program KUPS bisa optimal maka perlu dilakukan langkah berikut: 1) Sosialisasi KUPS di pusat dan
daerah oleh Kemtan, Bank, Dinas/Pemda, Asosiasi/Kelompok Peternak.
2) Pemetaan daerah yang berpotensi menyerap program KUPS.
3) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan KUPS antara Kementan, Kemenkeu, Perbankan, Pemda dan stakeholders terkait.
4) Monitoring ketersediaan bibit ternak yang akan dibeli dengan modal kredit KUPS di dalam dan luar negeri dengan kualitas yang memadai dan harga yang kompetitif.
5) Identifikasi dan klarifikasi pelaksana dan pemanfaatan KUPS.
6) Pembinaan dan pengawasan pelak-sanaan KUPS secara berjenjang.
7) Koordinasi dengan Pemda dalam pengalokasian APBD/DAK/DAU untuk dana penjaminan KUPS pada bank daerah.
8) Pengintegrasian program KUPS dalam program SMD (sarjana membangun desa).
d. Mengalokasikan Lahan Khusus hijauan Pakan Ternak
Pemerintah pusat membuat payung hukum untuk mengawal Pemerintah Daerah agar mengalokasikan lahan untuk wilayah peternakan di dalam Rencana Umum Tata Ruang (RUTR). Sapi impor dengan potensi genetik yang tinggi hanya akan berproduksi dengan baik pada lingkungan dan pemberian pakan yang sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu pengembangan sapi perah impor, memerlukan lahan khusus untuk hijauan pakan ternak. Kebutuhan
ternak sapi akan hujauan segar menurut perkiraan aksar yaitu 10% dari berat badan per hari per ekor. Apabila berat seekor sapi perah 600 kg, maka kebutuhan hijauan per hari adalah 60 kg, jadi kebutuhan akan hijauan per tahun 365 x 80 kg = 21,9 ton. Berdasarkan perhitungan tersebut berarti rumput raja dapat menampung 49 ekor sapi perah/ ha/tahun (http://serdangbedagaikab.go.id/indonesia/images/keputusan/rumput.pdf, 2010).
Program penyediaan lahan untuk rumput dilakukan melalui bebe-rapa cara:1) Pemanfaatan Lahan gontai. Di
tingkat daerah, pemanfaat lahan gontai (absente land) untuk rumput budidaya sangat memungkinkan dilakukan. Kebijakan ini mengadopsi kebijakan ketika krisis moneter 1997, dimana petani dibolehkan menanam sayuran pada lahan tidur. Pemanfaatan lahan gontai dilakukan melalui sistem kontrak pemilik dengan peternak dalam jangka waktu minimal 3 tahun, sesuai dengan masa produksi tanaman rumput.
2) Memanfaatkan kawasan hutan yang di atur dalam izin pengembangan silvopastura agar dapat diberikan kepada perorangan maupun korporasi.
e. Pendampingan Peternak Melalui Program Sarjana Membangun Desa
Pendampingan masih sangat diperlukan bagi peternak rakyat terutama dalam hal pemberian pakan berkualitas, penanganan kesehatan sapi, sanitasi pemerahan, pencatatan (recording) sistem informasi sapi perah Indonesia (SISI), dan pendeteksian birahi.
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011 - 217
Pendampingan peternak rakyat bisa melalui Program Sarjana Membangun Desa (SMD), yang sekaligus menjadi agen pembaharuan. Program SMD dilakukan dengan cara pemberian kredit murah jangka panjang (seperti KUPS) dan atau modal abadi (dalam bentuk bantuan sosial) dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah kepada kelompok peternak yang dimotori oleh peternak berpendidikan minimal sarjana/D3 Peternakan/Keswan yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu.
f. Kredit Pengembangan Industri Pengolahan SSDN Skala Kecil
Kredit khusus industri pengolahan susu perlu digulirkan untuk mendorong tumbuhnya pengolahan skala kecil, dan industri-industri skal kecil seperti ini diharapkan bisa menjadi kompetitor IPS dalam pembelian susu segar dari peternak. Industri pengolahan skala kecil, bisa berperan sebagai penampung susu segar dari peternak, sehingga lokasinya hendaknya berdekatan dengan cluster peternak. Sebagai pengelola adalah lembaga yang berkomitmen terhadap kesejahteraan peternak seperti kelompok peternak atau koperasi. Target pasar susu hasil olahan industri tersebut adalah captive market seperti program school milk dan masyarakat umum di sekitar lokasi peternakan.
g. Pendampingan dan Pengawasan Mutu hasil Produk
Susu siap konsumsi hasil pengolahan industri skala kecil masih dalam bentuk cair, sehingga memerlukan penanganan yang teliti agar tidak rusak dan tercemar bakteri. Pendampingan proses penanganan
susu dan pengawasan mutu produk, lebih diperketat untuk menjamin keamanan pangan. Pelatihan mengenai Hazard Analysis And Critical Control Points (HACCP) perlu diberikan kepada petugas operator pengolahan susu untuk meningkatkan kemampuan penanganan susu secara higienis.
h. Pelatihan Teknik Pengolahan Susu
Agar industri pengolahan susu skala kecil yang dikelola kelompok peternak/koperasi, bisa menghasilkan produk olahan susu segar yang lebih bervasiasi, maka perlu dilakukan pelatihan teknologi pengolahan susu. Pelatihan juga diberikan kepada industri makanan rumah tangga yang menggunakan bahan baku susu segar seperti karamel dan dodol susu. Dengan demikian, pasar susu segar bisa lebih luas. Disamping itu, untuk meningkatkan kapasitas pemasaran, pelatihan manajemen marketing perlu diadakan secara periodik kepada pelaku persusuan.
i. Pengaturan Rasio Bahan Baku SSDN Dan Impor Bagi IPS
Selama ini IPS masih berperan sebagai penyerap susu segar dalam negeri (SSDN) sekaligus menjadi importir utama bahan baku susu. Niat Pemerintah untuk meningkatkan produksi SSDN dan mengurangi impor terkait langsung dengan kedua peran IPS tersebut. Setelah kewajiban peternak menghasilkan susu berkualitas terpenuhi, maka menjadi kewajiban IPS untuk menampung SSDN dan membatasi impor bahan baku. Diperlukan payung hukum setingkat Menteri, agar IPS bisa konsisten dengan kewajibannya tersebut.
218 - Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011
j. Meningkatkan captive market untuk SSDN
Pengembangan SSDN harus diikuti dengan pengembangan pasar untuk SSDN. Susu segar mempunyai komposisi gizi sangat lengkap untuk membentuk generasi berkualitas. Di sisi lain pemerintah memiliki kewajiban menciptakan generasi yang sehat dan cerdas. Melalui program school milk yang menjadi kebijakan pemerintah pusat bagi murid-murid TK dan SD, dapat meningkatkan konsumsi susu segar sekaligus membantu peternak dalam memasarkan produknya. Untuk mendukung pelaksanaan program school milk di luar Pulau Jawa, diperlukan pula program pengembangan industri sapi perah atau produksi susu segar di daerah tersebut.
k. Peningkatan Efisiensi Dan Trans-paransi KUD Dan IPS
Peran koperasi sebagai perantara antara peternak dengan IPS, harus semakin berpihak pada kesejahteraan peternak. Beberapa koperasi dan IPS beroperasi dengan biaya tinggi, dan biaya tersebut dibebankan pada peternak melalui pemotongan harga beli susu oleh koperasi dan IPS. Kontrol yang ketat terhadap kinerja koperasi dan IPS diperlukan untuk mengefisienkan kinerja kedua lembaga tersebut. Kontrol juga dilakukan terhadap transparansi koperasi dan IPS dalam menentukan kualitas susu yang dihasilkan peternak, melalui lembaga independen yang menetapkan kualitas susu segar peternak di TPS (tempat penampungan sementara).
2. Program Pendukung a. Penanggulangan Gangguan Repro-
duksi dan Pelayanan Kesehatan hewan
Kegiatan ini ditargetkan untuk mengurangi tingkat kegagalan reproduksi sapi betina produktif yang telah dikawini/diinseminasi, dengan melaksanakan kegiatan operasional penanggulangan gangguan reproduksi, dan peningkatan pelayanan kesehatan hewan. Penanganan gangguan reproduksi dilakukan melalui pemeriksaan akseptor terhadap status penyakit Brucellosis (khusus di daerah yang belum bebas Brucellosis), peningkatan kualitas SDM yang menangani penyakit reproduksi, pengadaan obat-obatan dan hormonal, penanganan ternak yang mengalami gangguan reproduksi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
Peningkatan pelayanan kesehatan hewan dilakukan dengan cara pembangunan pusat kesehatan hewan di wilayah padat ternak, pemeriksaan, identifikasi, dan pemetaan kasus parasit internal dan kematian pedet; pengadaan obat-obatan parasit internal, terapi antibiotika, dan penambah daya tahan; serta peningkatan pelayanan poskeswan terhadap penanganan mastitis dan brucellosisi. Tenaga paramedis dan kemampuan teknis petugas reproduksi perlu ditingkatkan.
b. Revitasilasi Pusat Pembibitan Sapi Perah dan Aplikasi SISI
Agar tidak terjadi penurunan kualitas bibit induk sapi perah, perlu dilakukan penguatan wilayah sumber bibit dan kelembagaan usaha
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011 - 219
pembibitan. Wilayah yang teridentifikasi potensial sebagai sumber bibit sapi (VBC = village breeding center) berdasarkan acuan ilmiah, diberlakukan program SISI (sistem identifikasi sapi perah Indonesia). Kelompok peternak perlu dilatih dan didampingi dalam rangka menerapkan program VBC berdasarkan prinsip Good Breeding Practice.
Unit Pelaksana Teknis (UPT) pembibitan perlu diperkuat dan dibentuk kerjasama sinergis antar UPT lingkup Kementerian Pertanian dalam rangka seleksi, penjaringan, dan penyediaan bibit sapi unggul. Selanjutnya ditetapkan standard mutu bibit melalui sertifikasi bibit untuk menjaga/ meningkatkan harga bibit di tingkat UPT maupun di tingkat peternak.
c. Peningkatan Personil Dan Kemam-puan Petugas Inseminasi Buatan (IB)
Kualitas bibit yang semakin baik dan populasi sapi yang semakin banyak harus didukung dengan peningkatan kemampuan dan jumlah inseminator yang memadai. Inseminator merupakan penentu utama keberhasilan IB, yang selanjutnya akan menentukan S/C rasio, calving interval dan masa produksi induk. Pada umumnya setiap koperasi memiliki petugas IB, yang bisa dilibatkan dalam program ini.
KESIMPULANKetergantungan yang sangat
tinggi terhadap bahan baku susu impor untuk memenuhi kebutuhan susu nasional memiliki beberapa kelemahan, antara lain: (1) menguras devisa negara; (2) tidak menjamin keamanan pangan jangka panjang, (3) meningkatkan pengangguran dan mengurangi kesejahteraan peternak
serta (4) menurunkan konsumsi susu segar yang berkualitas berbahan baku SSDN.
Namun upaya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi susu berbasis SSDN diperlukan kerjasama seluruh pemangku kepentingan industri per-susuan mulai dari hulu sampai hilir. Peran pemerintah sangat diperlukan pada setiap tingkatan usaha tersebut. Pada tingkat hilir, permasalahan utamanya adalah penyediaan sarana produksi (bibit sapi perah, pakan konsentrat dan hijauan). Support pemerintah sangat diperlukan, khususnya dalam pembibitan, subdisi pakan konsentrat serta penyediaan lahan khusus hijauan makanan ternak (HMT).
Di tingkat on farm, pemerintah masih perlu memerlukan pembinaan dan pendampingan kepada peternak. Pembinaan peternak dilakukan oleh penyuluh, atau atas rekomendasi pemerintah oleh koperasi atau IPS, melalui program SCR atau SMD misalnya. Pembinaan tersebut perlu dilakukan secara kontinyu untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas susu yang dihasilkan peternak rakyat.
Pada tingkat pemasaran, peme-rintah berperan dibidanga pengawasan selama prosessing dan pengawasan kualitas produk susu siap konsumsi. Penciptaan captive market (seperti school milk) untuk memperluas pasar SSDN sekaligus program peningkatan kualitas SDM, memerlukan dukungan politik dari pemerintah. Kewajiban membeli SSDN bagi IPS dengan harga dasar yang bisa memberikan keuntungan bagi peternak, juga perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan penyerapan SSDN.
Akses memperoleh modal murah untuk pengembangan industri persusuan sangat diperlukan terutama
220 - Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011
di tingkat on farm. Kredit bersubsidi yang ditawarkan oleh pemerintah seringkali sulit diakses oleh peternak karena persyaratannya tidak bisa dipenuhi. Biaya-biaya tambahan selama mengelola kredit bersubsidi pun dibebankan kepada peternak, sehingga biaya modal yang riil dikeuarkan peternak menjadi semakin tinggi.
Tidak kalah penting adalah prinsip kerjasama yang adil dan saling menguntungkan antara peternak, koperasi dan IPS. Kerjasama yang baik antara ketiganya sangat diperlukan untuk kelancaran program peningkatan produksi SSDN. Pengukuran kualitas susu segar untuk menetapkan harga beli dari peternak, perlu lebih transparan dan bertujuan memberikan insentif bagi peternak untuk meningkatkan kualitasnya.
DAFTAR PUSTAKAAnonim. (2006). “Frisian flag perluas
jalur distribusi”. Diakses dari http://www.wartaekonomi.com/detail.asp?aid=7167&cid=18 pada tanggal 27 Jan 2010.
Anonim. (2009). “Peternak Sapi Khawatir Bea Impor Susu Turun” Diakses dari http://gudeg.net/id/news/1001/news pada tanggal 19 Juni 2009
Badan Pusat Statistik. 2010. Perkembangan Harga Pangan. Badan Pusat Statistik. Jakarta
Boediyana, Teguh. (2008). “Menyongsong agribisnis persusuan yang prospektif di tanah air”. Trobos, No 108 September 2008 Tahun VIII.
Direktorat Pemasaran Domestik. (2010). Perkembangan Harga Susu Segar di Tingkat Peternak (Produsen) periode Januari -
April Tahun 2010. Kementrian Pertanian. Jakarta.
Direktorat Budidaya Ternak Ruminansia. (2010). Road Map Revitalisasi Persusuan Nasional. Direktorat Budidaya Ternak Ruminansia Tahun 2010-2014. Kementrian Pertanian. Jakarta.
Direktorat Jenderal Peternakan. (2010). Buku Statistik Peternakan. Direktorat Jenderal Peternakan, Kementerian Pertanian. Jakarta.
Ditjen Perdagangan Dalam Negeri. (2010). “Perkembangan Harga Bahan Pokok”. Dokumen yang belum dipublikasikan.
Institut Pertanian Bogor. (2010). “Model Penciptaan Pengetahuan Untuk Meningkatkan Keunggulan Bersaing Koperasi Susu di Indonesia. Diakses dari http://repository.ipb.ac.id/bitstream/hand le /123456789/46508/B A B % 2 0 I % 2 0Pendahuluan_%202011asu.pdf?sequence=4, pada tanggal 15 Juni 2010
Kementerian Keuangan. (2007). Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI). Kementerian Keuangan, Jakarta.
Kementerian Pertanian. (2009). Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS). Direktorat Jenderal Peternakan. Kementerian Pertanian. Jakarta.
Kementerian Pendidikan Nasional. (2010). Contoh Mekanisme School Milk. Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta.
Kementerian Pertanian. (2010). Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010-2014
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011 - 221
Pambudy, R. (2009). “Impor-pangan-yang-menjebak/ Pemerintah Kenakan Tarif Bea Masuk Impor Susu”. Diakses dari http://agroindonesia.co.id/2009/09/01/ tanggal 1 September 2009.
Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. (2010). “King Grass (Rumput Raja)”. Diakses dari http://serdangbedagaikab.go.id/indonesia/images/keputusan/rumput.pdf, pada tanggal 16 Juni 2010
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
Peraturan Presiden RI N0 62 Tahun 2008 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2007 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu.
Peraturan Presiden RI N0 28 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Industri Nasional
Peraturan Menteri Keuangan N0 131/PMK.05/2009 Tentang Kredit Usaha Pembibitan Sapi dan Peraturan Menteri Pertanian N0 40/Permentan/PD-400/9/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan kredit Usaha Pembibitan sapi
Pusat Data Perdagangan. (2010). Data Impor Susu Indonesia. Pusat Data Perdagangan, Kementerian Perdagangan. Jakarta
Sukria H. Ahmad dan Rantan Krisnan. (2009). Sumber dan Ketersediaan Bahan Baku Pakan di Indonesia. IPB Press. Bogor.
Tim Satgas PSDS IPB. (2010). “Road Map Skenario PSDS (Program Swasembada Daging Sapi) 2014”. Bahan Presentasi. IPB. Bogor.
“Undang-undang No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan”
www.understandingdairymarket.com
222 - Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011
PENDAHULUANPada tanggal 11 Agustus 2010,
Presiden Amerika Serikat Barack Obama telah menandatangani undang-undang perdagangan yang mengatur perubahan jenis barang impor dan besarnya tarif bea masuk impor yang disebut H.R.4380, dalam the U.S. Manufacturing Enhancement Act of 2010. Undang-undang tersebut terbit atas sponsor Chairman Sender Levin (D-Michigan) pada tanggal 16 Desember 2009. Undang-undang ini awalnya disebut Miscellaneous Trade and Technical Corrections Act of 2009 atau disebut juga Milcellaneous Tariff Bill (MTB),
yang memperoleh dukungan lebih dari 130 industri, pelaku bisnis dan asosiasi di Amerika Serikat, antara lain National Association of Manufacturers, American Apparel and Footwear Association, Outdoor Industry Association, U.S. Chamber of Commerce dan Society of Chemical Manufacturers and Affiliates. Undang-Undang ini sebelum diterbitkan, telah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari U.S. House of Representative pada tanggal 21 Juli 2010 dan U.S. Senate pada tanggal 27 Juli 2010 (Arif Fadillah, 2010).
Tujuan dari diterbitkannya undang-undang H.R.4380, the U.S.
DAMPAK PENERAPAN H.R.4380, DALAM The u.S. mANufACTuRiNgeNhANCemeNT ACT of 2010 BAGI INDONESIA
Oleh : Aziza Rahmaniar Salam
Naskah diterima : 7 November 2011Disetujui diterbitkan : 12 Desember 2011
AbstractThis study aims at reviewing the Indonesia trade performance on several
products included in the list of the new Act, the U.S Manufacturing Enhancement Act of 2010. Using secondary data collected from The Central Board of Statistics and the World bank, it was found that Indonesia has benefits from the tariff reduction facility under the US Manufacturing Enhancement Act of 2011. The benefit is in increasing non-oil product exports to US. Also,it is shown that there is an increasing Indonesia’s shares in US market especially for products with tariff heading 2934.99, 3808.93, 3907.99, 3917.40, 4016,99 and 4202.92
Keywords: Indonesia Trade Performance, Tarif Reduction
JEL Classification: F13
1 Peneliti pada Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta. E-mail : [email protected]
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011 - 223
melindungi lapangan kerja dan sekaligus menurunkan biaya operasional pabrik-pabrik dan industri di Amerika Serikat, dengan mengurangi, menunda, menghilangkan dan menaikkan bea masuk impor sampai dengan tanggal 31 Desember 2012. Produk-produk yang masuk dalam undang-undang ini adalah produk-produk yang tidak diproduksi di Amerika Serikat, atau produk-produk yang tidak bersaing dengan produk dalam negeri yang dibutuhkan oleh industri Amerika Serikat dalam memproduksi produknya, sehingga produk industri Amerika Serikat akan lebih bersaing dalam harga. Disisi lain, untuk melindungi produk-produk industri dalam negeri Amerika Serikat, dinaikkan juga bea masuk impor sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 (http://www.govtrack.us/congress/bil ltext.xpd?bill=h111-4380, 2010)
Penerbitan undang-undang ini dimaksudkan untuk mengganti undang-undang Consolidated omnibus budget Reconsiliation Act of 1985 (COBRA) yang ditujukan untuk memperpanjang berlakunya biaya proses di kepabeanan dan untuk pengeluaran produk impor tertentu sampai dengan tanggal 14 Juni 2018 dan 28 Juni 2018. Disamping merubah undang-undang Consolidated Omnibus budget Reconsiliation Act of 1985 (COBRA), penerbitan undang-undang H.R.4380,dalam the U.S. Manufacturing Enhancement Act of 2010, juga merubah the Corporate Estimate Tax Shift Act of 2009 untuk meningkatkan perkiraan pembayaran pajak asset perusahaan paling tidak $ 1 milyar USD dalam kuartal ke tiga 2014 sebesar 0,75 % (Arif Fadillah, 2010).
Undang-undang H.R.4380, the U.S. Manufacturing Enhancement Act of 2010 ini berlaku 15 hari setelah ditanda tanganinya menjadi U.S. Public Law No. 111-227 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Dengan berlakunya undang-undang ini, para importir dapat meminta kembali bea masuk yang telah dibayarkan untuk produk-produk yang bebas bea masuk atau pengurangan bea masuk untuk impor yang dilakukan antara 1 Januari 2010 sampai dengan 15 hari diberlakukannya undang-undang H.R.4380, the U.S. Manufacturing Enhancement Act of 2010 (section 3001(b)).
Dengan berlakunya the U.S Manufacturing Enhancement Act of 2010, dipastikan berdampak bagi peningkatan nilai beberapa produk impor dari Indonesia. Hal ini karena akan digunakan sebagai bahan baku industri dalam negeri Amerika Serikat, sehingga tercipta lapangan kerja bagi masyarakat Amerika Serikat. Sedangkan produk impor asal Indonesia yang berupa barang konsumsi dan tidak memberikan dampak bagi pengembangan industri dan perluasan lapangan kerja dalam negeri Amerika Serikat, seperti alas kaki akan menghadapi persaingan di pasar dalam negeri Amerika Serikat.
Oleh karena itu, suatu kajian untuk menelusuri bagaimana kinerja perdagangan beberapa produk ekspor Indonesia ke Amerika Serikat yang masuk dalam daftar the U.S Manufacturing Enhancement Act of 2010 perlu dilakukan seperti yang diungkapkan dalam artikel ini. Adapun data-data yang digunakan dalam kajian ini adalah data primer yaitu nilai ekspor Indonesia ke
224 - Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011
Amerika Serikat yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) periode tahun 2005 hingga Januari – Juli 2010. Disamping itu juga digunakan data nilai impor Amerika Serikat yang bersumber dari World Integrated Trade System (WITS).
Produk Dalam U.S Manufacturing enhancement act of 2010
Produk-produk yang bea masuknya dikurangi maupun yang dinaikkan dalam U.S Manufacturing Enhancement Act of 2010 sebanyak 95 pos tarif yang tercakup dalam chapter 99 buku tarif bea masuk Amerika Serikat. Dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI), produk dikelompokkan dalam chapter 01 sampai dengan chapter 98, sehingga Indonesia tidak mengenal chapter 99. Adapun dari 95 pos tarif tersebut, 82 pos tarif diantaranya mengalami penurunan tarif bea masuk dan sisanya sebanyak 13 pos tarif mengalami kenaikan tarif bea masuknya.
Chapter 99 dalam the U.S Manufacturing Enhancement Act of 2010 maupun chapter 98 dalam BTBMI dimaksudkan untuk penggunaan khusus oleh contracting party (negara pihak konvensi HS) dimana ketentuan akan chapter tersebut sesuai dengan ketentuan nasional masing-masing negara. Konvensi HS tidak mengatur mengenai ketentuan penggunaan chapter 98 dan chapter 99 sehingga tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur implementasinya. Oleh karena itu, negara pihak konvensi HS tidak diwajiban untuk menotifikasi ke World Custom Oragnization (WCO) mengenai
pembentukan / penggunaan kedua chapter tersebut untuk kepentingan nasionalnya (Craig Clark, 2010).
Beberapa jenis barang impor yang bea masuknya dikurangi antara lain : reusable grocery bags, automobile parts, digital camera lenses, fibers, yarns, chemicals, microwaves, plastic fittings, herbicides dan beberapa produk penolong lainnya yang dibutuhkan dan dipergunakan oleh pabrikan di Amerika Serikat.
Adapun produk impor yang dilindungi dengan menaikkan bea masuk impornya adalah produk alas kaki seperti sepatu untuk anak, wanita dan pria yang terbuat dari bahan tesktil dan kulit, tas perlengkapan golf, rem untuk sepeda, 12 volt lead-acid storage batteries, aspirin dan produk lainnya.
Berdasarkan uraian barang, HS dalam chapter 99 mengikuti sub heading chapter 28, 29, 32, 38, 39, 40, 42, 51, 54, 55, 84 dan 85, dimana terdapat beberapa pos tarif yang mengacu pada pos tarif yang sama pada beberapa chapter diatas, sehingga jumlah pos tarif yang mengalami perubahan tarif bea masuknya baik yang mengalami penurunan/penundaan maupun kenaikan tarif bea masuknya menjadi 54 pos tarif, dengan rincian 50 pos tarif mengalami penurunan tarif bea masuk dan 4 pos tarif mengalami kenaikan tarif bea masuk.
Dampak U.S Manufacturing enhancement act of 2010
Terbitnya the U.S Manufacturing Enhancement Act of 2010 dapat berdampak positif bagi beberapa produk ekspor Indonesia yang selama
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011 - 225
ini diekspor ke Amerika Serikat, tetapi dapat juga berdampak negatif. Analisis dampak diterbitkannya UU tersebut dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu pertama, dampaknya terhadap kinerja ekspor produk Indonesia ke Amerika Serikat. Kedua, analisis dilakukan terhadap posisi binding tarif Amerika Serikat di WTO.
Neraca perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat pada tahun 2009 menunjukkan angka yang positif walaupun menurun dibandingkan dengan tahun 2008 yaitu US$ 3.766,1 juta di tahun 2009 dari sebelumnya US$ 5.156,8 juta. Ekspor Indonesia didominasi oleh ekspor non migas.
Berdasarkan kinerja ekspor Indonesia ke Amerika Serikat, dari 50 pos tarif yang mengalami penurunan tarif bea masuk, hanya 29 pos tarif yang Indonesia mengekspor ke Amerika Serikat . Begitu pula dari 4 pos tarif yang mengalami kenaikan tarif bea masuk, hanya 3 pos tarif yang Indonesia mengekspor ke Amerika Serikat. Dari 29 pos tarif yang tarif bea masuknya diturunkan, hanya 1 pos tarif yang mempunyai tren ekspor positif selama periode 2005-2009 yaitu pos tarif 3824.90 (products, preparation and residual products of the chemical or allied industries, incl, those consisting of mixtures of natural products) yaitu sebesar 547.06%.
Pangsa ekspor Indonesia di pasar Amerika Serikat untuk pos tarif 3824.90 pada tahun 2008 sebesar 10,35 % (berada di posisi ke 4) dengan pesaing utama Argentina, Kanada dan Jerman serta China di posisi ke 5. Namun, pada tahun 2009 share Indonesia di Amerika
Serikat untuk produk yang sama turun menjadi 1,06% (posisi ke 16). Pesaing lain yang muncul disamping Argentina, Kanada, Jerman dan china adalah Jepang, Inggris, Perancis, Malaysia, Swiss, Meksiko, Korea, Italia dan Belgia.
Disamping pos tarif 3824.90 (products, preparation and residual products of the chemical or allied industries, incl, those consisting of mixtures of natural products), terdapat 6 pos tarif lainnya yang walaupun trend ekpor selama periode 2005-2009 negatif. Namun pada periode Januari- Juli 2010 nilai dan volume ekpornya naik dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2009 yaitu pos tarif 2934.99 (Nucleic acids&their salts, whether/not chemically defined,n.e.s.; other heterocyclic compounds,n.e.s), pos tarif 3808.93 (herbicides, anti-sprounting products and plant-growth regulators, put up in forms/packings for retail sale/as preparations/articles), pos tarif 3907.99 (plyesters nesoi, saturated in primary form), pos tarif 3917.40 (fitting for tubes, pipes and hoses of plastics), pos tarif 4016.99 (articles of vulcanized rubber other than hard rubber, nesoi) dan pos tariff 4202.92 (container bags, boxes, caese and satchels nesoi, with outer surface of plastics sheeting or of textile materials).
Pangsa Indonesia ke Amerika Serikat untuk pos tarif 2934.99 (Nucleic acids&their salts, whether/not chemically defined,n.e.s.; other heterocyclic compounds,n.e.s) pada tahun 2008 sebesar 0,06% (posisi ke 22) meningkat menjadi 0,14% pada tahun 2009 (posisi 18) dengan pesaing utama Irlandia,
226 - Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011
Belgia, Inggris, Jepang dan Perancis. Adapun share Indonesia untuk
produk herbicides, anti-sprounting products and plant-growth regulators, put up in forms/packings for retail sale/as preparations/articles dalam pos tarif 3808.93 ke pasar Amerika Serikat sebesar 1,56% / posisi ke 10 pada tahun 2008 dengan pesaing utama China, Israel, Kanada, Jerman dan Inggris, dan turun menjadi 0,14% pada tahun 2009 (posisi ke 17). Untuk pos tarif 3907.99, pangsa Indonesia di pasar Amerika Serikat pada tahun 2008 (posisi ke 27) sebesar 0,01% dan di tahun 2009 mengalami penurunan menjadi kurang dari 0,01% (posisi ke 106) dengan pesaing utama Jerman, Jepang, Inggris, Kanada dan Belanda.
Untuk pos tarif 3917.40 (fitting for tubes, pipes and hoses of plastics), pangsa Indonesia ke Amerika Serikat pada tahun 2008 kurang dari 0,01%. Sedangkan untuk pos tarif 4016.99 (articles of vulcanized rubber other than hard rubber, nesoi), share Indonesia ke Amerika Serikat pada tahun 2008 sebesar 0,47% dan naik menjadi 0,58% pada tahun 2009, dan pos tarif 4202.92 (container bags, boxes, caese and satchels nesoi, with outer surface of plastics sheeting or of textile materials), pangsa Indonesia ke Amerika Serikat pada tahun 2008 sebesar 0,26% dan pada tahun 2009 naik menjadi 0,51%. Detil dari ekspor Indonesia ke Amerika Serikat selama periode tahun 2005 – 2010 yang tarif bea masuknya diturun-kan dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Data Ekspor (29 Pos Tarif) Indonesia Ke Amerika Serikat Tahun 2005 – 2010 (Januari – Juli) Yang Tarif Bea Masuknya Diturunkan
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011 - 227
Dari 3 pos tarif yang tarif bea masuknya dinaikkan berdasarkan the U.S Manufacturing Enhancement Act of 2010, nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat sangat kecil. Sehingga kenaikan tarif atas 3 pos tarif tersebut tidak akan memberikan dampak yang besar terhadap ekspor Indonesia (Tabel 2).
Tujuh pos tarif (HS 2934.99, 3824.90, 3907.99, 4016.99, 3808.93, 3917.40 dan 4202.92), yang berpeluang bagi Indonesia untuk mengembangkan ekspornya ke Amerika Serikat me-rupakan pos tarif yang besaran tarif bea masuknya di bound dalam Schedule XX di World Trade Organization (WTO).Besaran bound tarif untuk 7 pos tarif tersebut bervariasi antara 2,8 % hingga
17,6 %. Penurunan atau penghapusan tarif yang telah di bound di WTO, tidak bertentangan dengan aturan WTO.
Maksud dari kebijakan meng-hilangkan besaran tarif atau menjadikan tarif menjadi nol % untuk ke-7 produk-produk tersebut hingga 31 Desember 2012 dapat diindikasikan salah satu strategi Amerika Serikat menyelesaikan krisis ekonomi yang melanda negaranya akibat mengalami masalah kemacetan kredit perumahan kelas dua (Subprime Mortgage) pada akhir 2007 yang sampai saat ini tak kunjung mereda. Hal ini menyebabkan bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar Amerika Serikat, seperti General Motor, Lehman Brothers dan perusahaan lain yang
Sumber : Data Ekspor (BPS, 2005- Juli 2010)
228 - Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011
awalnya memberikan pemasukan besar bagi negara. Pengangguran yang makin banyak juga memperparah keadaan ekonomi di Amerika Serikat yang secara otomatis akan menurunkan daya beli masyarakat Amerika Serikat. Adanya krisis ini, Amerika Serikat membutuhkan bantuan berupa materi dan moril negara-negara lain untuk menopang perekonomiannya yang sedang bermasalah. Jatuhnya perekonomian Amerika Serikat ini berdampak keseluruh dunia sehingga negara-negara yang terkena imbasnya turut membantu Amerika Serikat
Dengan tarif bea masuk yang rendah bahkan nol % diharapkan mereka dapat memperoleh bahan baku yang murah tanpa pajak bea masuk, sehingga bisa menghidupkan kembali sektor real mereka dan pada akhirnya mampu menyerap kembali tenaga kerja dan menghasilkan produk akhir yang lebih murah yang sesuai dengan daya beli masayarakat Amerika Serikat saat ini.
kesimPulanKinerja ekspor 7 produk
Indonesia yang masuk dalam daftar the U.S Manufacturing Enhancement Act of 2010 menunjukkan tren yang positif. Untuk pos tarif 3824.90 (products, preparation and residual products of the chemical or allied industries, incl, those consisting of mixtures of natural products) tren eskpor selama periode tahun 2005-2009 sebesar 547.06%, dengan pesaing utama Argentina, Kanada dan Jerman serta China, Jepang, Malaysia. Untuk pos tarif 2934.99 (Nucleic acids&their salts, whether/not chemically defined,n.e.s.; other heterocyclic compounds,n.e.s), pangsa ekspor Indonesia di Amerika Serikat sebesar 0,14% pada tahun 2009 dengan pesaing utama Irlandia, Belgia, Inggris, Jepang dan Perancis. Adapun share Indonesia untuk produk herbicides, anti-sprounting products and plant-growth regulators, put up in forms/packings for retail sale/as preparations/articles dalam pos tarif
Tabel 2. Data Ekspor (3 Pos Tarif) Indonesia Ke Amerika Serikat Tahun 2005 – 2010 (Januari – Juli) Yang Tarif Bea Masuknya Dinaikkan
Sumber : Data Ekspor (BPS, 2005- Juli 2010)
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011 - 229
3808.93 sebesar 10,14% pada tahun 2009 dengan pesaing utama China, Israel, Kanada, Jerman dan Inggris.
Untuk pos tarif 3907.99, pangsa Indonesia di pasar Amerika Serikat pada tahun 2009 mengalami penurunan menjadi kurang dari 0,01 % (posisi ke 106), dengan pesaing utama Jerman, Jepang, Inggris, Kanada dan Belanda dan untuk pos tarif 3917.40 (fitting for tubes, pipes and hoses of plastics), pangsa pasar Indonesia di Amerika Serikat pada tahun 2008 kurang dari 0,01 %. Sedangkan untuk pos tarif 4016.99 (articles of vulcanized rubber other than hard rubber, nesoi) share Indonesia ke Amerika Serikat naik menjadi 0,58 % pada tahun 2009, dan pos tarif 4202.92 (container bags, boxes, caese and satchels nesoi, with outer surface of plastics sheeting or of textile materials), pangsa Indonesia ke Amerika pada tahun 2009 naik menjadi 0,51%.
Indonesia dapat memanfaat-kan fasilitas penurunan tarif bea masuk dalam the U.S Manufacturing Enhancement Act of 2010 untuk meningkatkan ekspor non migas Indonesia ke Amerika Serikat, dan memanfaatkan pasar di Amerika Serikat yang selama ini share Indonesia kecil
dan semakin menurun, terutama untuk produk-produk dalam pos tarif 2934.99, 3808.93, 3907.99, 3917.40, 4016.99 dan 4202.92.
DAFTAR PUSTAKA Arif Fadillah. Nota dinas KBRI Washinton.
2010Badan Pusat Statistik. Data Ekspor
periode 2005-2010Craig Clark. email dari Deputy Director
Tarif and Trade Affairs Directorate, World Customs Organization. 17 November 2010.
World Trade Organization (WTO). Schedule XX Amerika Serikat. Diunduh dari http://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/usa_e.htm tanggal 5 Januari 2011.
World bank. World Integrated Trade System (WITS) (2008): https://wits.worldbank.org/WITS/WITS/. Diunduh tanggal 15 Oktober 2010
----- H.R.4380, the U.S. Manufacturing Enhancement Act of 2010. Diunduh dari http://www.govtrack.us/congress/billtext.xpd?bill=h111-4380 tanggal 28 September 2010.
230 - Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011
Mitra Bestari :
Prof. Dr. Abuzar Asra, M.ScProf. Dr. Carunia Mulya Firdausy, MADr. Ir. Hartoyo, M.ScProf. Dr. Masyhuri, M.ScProf. Dr. Rina OktavianiIr. Ronny Natawijaya, Ph.DSjamsu Rahardja, Ph.DProf. Drs. Sukarna Wiranta, MAProf. Zainudin Jafar, Ph.D