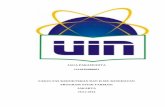METHAREZQI SUCI ARSIH-FKIK.pdf - Institutional Repository ...
LIAZUL KHOLIFAH-fkik.pdf - Institutional Repository UIN Syarif ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of LIAZUL KHOLIFAH-fkik.pdf - Institutional Repository UIN Syarif ...
FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN
TERJADINYA KELELAHAN PADA IBU MENYUSUI ≤ 6 BULAN
DI KELURAHAN PISANGAN CIPUTAT TIMUR
TAHUN 2013
SKRIPSI
OLEH
LIAZUL KHOLIFAH
108101000063
PEMINATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1434 H./2013 M.
iii
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
Skripsi, Juli 2013
Liazul Kholifah, NIM. 108101000063
Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Terjadinya Kelelahan pada Ibu
Menyusui ≤ 6 Bulan di Kelurahan Pisangan Ciputat Timur Tahun 2013
xiv + 140 halaman, 25 tabel, 10 gambar, 4 lampiran
ABSTRAK
Menyusui merupakan kegiatan yang dilakukan selama berjam-jam dan berkali-
kali setiap harinya oleh ibu pasca melahirkan. Satu gejala yang sering dilaporkan ibu
yang baru pertama kali menyusui bayinya yang membuat ibu memperpendek
lamanya dalam menyusui adalah kelelahan (fatigue). Kelelahan yang dirasakan oleh
ibu-ibu selama menyusui menurunkan produksi ASI selama bulan pertama
postpartum dan menjadi faktor yang utama untuk menyapih bayinya.Dari hal tersebut
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang
berhubungan dengan terjadinya kelelahan pada ibu menyusui ≤ 6 bulan di Kelurahan
Pisangan Ciputat Timur tahun 2013 tersebut.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain studi cross-
sectional. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh ibu menyusui ≤ 6
bulan di Kelurahan Pisangan Ciputat Timur berjumlah 38 orang berdasarkan data ibu
menyusui yang diperoleh dari seluruh posyandu di kelurahan pisangan. Variable yang
diteliti dalam penelitian ini adalah kelelahan pada saat menyusui, tingkat risiko
ergonomi postur menyusui, usia, kebiasaan merokok, status gizi, lama menyusui,
aktivitas fisik, dan faktor lingkungan (suhu, kebisingan, dan pencahayaan).
Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan metode wawancara, observasi dan
pengukuran langsung kepada responden.
Dari hasil penelitian diperoleh bahwa 92.1% ibu menyusui mengalami kelelahan.
Sedangkan dari hasil analisis bivariat tidak ditemukan adanya hubungan yang
bermakna antara semua variabel independen yang diteliti dengan terjadinya
kelelahan.Meskipun demikian, seluruh postur yang digunakan ibu saat menyusui
termasuk kategori berisiko. Ibu yang mengalami risiko ergonomi sedang 15,8% dan
ibu yang risiko ergonomi tinggi 84,2%.Sehingga disarankan sebaiknya diberikan
pelatihan kepada ibu menyusui maupun calon ibu menyusui tentang postur menyusui
yang benar meliputi posisi menyusui, pemilihan tempat menyusui dan alat bantu
dalam proses menyusui.
Kata Kunci : Kelelahan, Menyusui, ≤ 6 Bulan
Daftar Bacaan : 57 (1985-2012)
iv
SYARIF HIDAYATULLAH ISLAMICSTATE UNIVERSITY OF JAKARTA
FACULTY OF MEDICIAN AND HEALTH SCIENCE
PUBLIC HEALTH PROGRAM Thesis, July 2013
Liazul Kholifah, NIM. 108101000063
THE FACTORS ASSOCIATED WITH THE OCCURRENCE OF FATIGUE
BY BREASTFEEDING MOTHER ≤ 6 MONTHS IN PISANGAN VILLAGE
EAST CIPUTAT IN 2013
xiv + 140 pages, 25 tables, 10 pictures, 4 appendices
ABSTRACT
Breastfeeding is an activity that was undertaken by mother after childbirth for
many hours and many times. One of the often reported phenomenons by first
breastfeeding mothers is fatigue, so it causes them to shorten the duration of
breastfeeding. The fatigue that they have been felt can decrease the ASI production
during the first month of postpartum, and it becomes the main reason for the
breastfeeding mothers to wean their baby soon. So that the researcher was interested
in conducting a research on the factors associated with the occurrence of fatigue by
breastfeeding mother ≤ 6 month in Pisangan village East Ciputat in 2013.
This research is a quantitative research that used cross-sectional design. The
population and sample of the research was all breastfeeding mothers ≤ 6 month in
Pisangan village East Ciputat. There were 38 breastfeeding mothers. The total of the
breastfeeding mothers was got from the data of all posyandu in Pisangan village.
Some of analyzed variables were the fatigue when give breastfeeding, the risk level
of ergonomicsbreastfeeding posture, age, smoking habit, nutrient status, the duration
of breastfeeding, physic activity, and environment factors (temperature, noise, and
exposure). Some methods of collecting data were interview, observation and direct
measurement to the respondent.
The research result showed that 92.1% of the breastfeeding mothers had
fatigue. Whereas based on the bivariate analysis was not found a significance
relationship among all independent variables with the occurrence of fatigue. But, the
all postures that were used by mother when give breastfeeding included risk category,
because 15.8 % mothers were medium ergonomics risk and 84.2% mothers were high
ergonomics risk. So it suggested giving some training to the breastfeeding mothers
and candidate of the breastfeeding mothers about the right way of breastfeeding
posture, such as breastfeeding position, site selection of breastfeeding and the
equipment used in breastfeeding.
Key Words : Fatigue, Breastfeeding, ≤ 6 month
Reading List : 57 (1985-2012)
v
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, atas rahmat-Nyalah penulis dapat
menyelesaikan skripsi dengan judul “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan
Terjadinya Kelelahan Pada Ibu Menusui ≤ 6 Bulan di Kelurahan Pisangan Ciputat Timur
Tahun 2013”. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Baginda Rasulullah
Muhammad SAW yang membawa umatnya untuk senantiasa menapaki jalan yang
diridloi-Nya.
Skripsi merupakan tugas akhir perkuliahan berupa hasil penelitian yang
dilakukan oleh penulis untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM).
Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari
berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan
banyak terima kasih kepada:
1. Keluarga Besar saya, Ayahanda dan Ibunda tercinta, serta Mas Amirullaifa, Mbak
Aslichah, Adek M. Ubaidillah Hasan, si-kecil Sa’adatul Ukhrowiyatul Hasanah
yang tak henti-hentinya mendoakan dan mensuport.
2. Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan besar
kepada penulis untuk dapat melanjutkan studi formal ke Perguruan Tinggi
3. MA Darul Ulum berasan yang telah membekali penulis dengan ilmu-ilmu dan
memberi kesempatan kepada penulis untuk ikut serta dalam program beasiswa ke
Perguruan Tinggi
4. Ma’had Manba’ul Ulum yang telah membekali penulis dengan ilmu-ilmu agama
5. Prof. Dr. (hc) dr. M.K. Tadjudin, Sp. And.; selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan
Ilmu Kesehatan (FKIK);
6. Ibu Febrianti, M.Si, selaku Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat dan
stafnya;
7. Ibu Yuli Amran, SKM. MKM, selaku pembimbig I yang telah memberikan
bimbingan dan pengarahannya selama penyusunan skripsi ini;
vi
8. Ibu Iting Shofwati, ST. MKKK, selaku pembimbing II yang telah memberikan
bimbingan dan masukan selama penyusunan skripsi;
9. Penguji proposal skripsi, Ibu Ratri Cipta Ningtiyas, SKM. S.Sn.Kes, Ibu Raihana
N.Alkaff,M.MA dan Ibu Izzatu Millah,M.KKKyang telah membimbing dan
memberikan banyak koreksi dalam penyusunan skripsi;
10. Segenap bapak ibu dosen Kesehatan Masyarakat yang telah membagikan ilmu
pengetahuan dan memberikan pengarahannya selama prosesi akademi;
11. Staf Kesehatan Masyarakat dan FKIK yang membantu dalam hal administrasi
12. Pihak Kecamatan Ciputat Timur
13. Pihak Kelurahan Se-Kecamatan Ciputat Timur dan Ibu-Ibu kader yang dengan
senang hati telah membatu penulis dalam pengumpulan data
14. Sahabat-sahabati senaungan dan seperjuangan Dhevy, Eka, Eca, Tiwi, Iqbal,
Nadia, Ndud, Lilis yang telah membantu dalam pengumpulan data dan sharing
ilmu.
15. Sahabat-sahabati KOPRI PMII Cabang Ciputat yang selalu memberikan support.
16. Untuk para oponen dalam seminar proposal skripsi yang telah bersedia pusing
membaca dan memberi masukan untuk arah skripsi ini
17. Keluarga besar Stoopelth 2008 yang selalu menyemangati dan mengingatkan
18. Keluarga besar CSS MORA UIN JKT, khusunya Matrix’08
19. Serta kepada berbagai pihak yang turut mendukung dan membantu atas
terselesaikannya skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu.
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini, masih terdapat
banyak kekurangan baik dari segi penulisan maupun isi. Maka dari itu, penulis
berharap akan adanya penyusunan yang lebih baik untuk generasi mendatang.
Wassalamu’alaikum, Wr. Wb.
Jakarta, Juli 2013
Liazul Kholifah
vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama : LIAZUL KHOLIFAH
Tempat, TanggalLahir : Banyuwangi, 10 Februari 1989
JenisKelamin : Perempuan
Alamat : Dsn. Sumberagung, Ds.
Rejoagung RT 01 RW 02
Kec. Srono, Kab. Banyuwangi,
Prop. JawaTimur
Domisili : AsramaPutri PMII
CabangCiputat, JlIbnuTaimia
IV no 195 KomplekDosen UIN
SyarifHodayatullahKec.
CiputatTimur, Kota Tangerang
Selatan
Agama : Islam
Status Pernikahan : BelumMenikah
NomorHandphone : +62 85719522778
Email :[email protected]
RIWAYAT PENDIDIKAN
2008 – Sekarang S1-Program StudiKesehatanMasyarakat,
FakultasKedokterandanIlmuKesehatanUniversitas Islam Negeri
(UIN) SyarifHidayatullah Jakarta
2005 – 2008 Madrasah Aliyah (MA) DarulUlumBanyuwangi
2002 – 2005 Madrasah Stanawiyah (Mts) DarulUlumBanyuwangi
1996 – 2002 MI AL-Ma’arif Banyuwangi
PENGALAMAN MAGANG
Februari-Maret 2012 Occupational Healt Station-HSE (Health, Safety, and Environment)
PT Pertamina RU V Balikpapan
viii
PENGALAMAN ORGANISASI
2006 – 2008 SekretarisBahstulMasailPonPesManbaulUlum
2006 – 2008 RoisJam’iyah Al-FalahPonPesManbaulUlum
2006 – 2008 KoordinatorDepartemenDakwahPonPesManbaulUlum
2008 – 2009 KetuaGedung A AsramaPutri UIN SyarifHidayatullah Jakarta
2009 – 2010 StafDepartemenKemahasiswaanBadanEksekutifMahasiswaJurusan
(BEM-J) KesehatanMasyarakat
2009 – 2011 SekretarisDepertemenKeislamanCommunity of Santri Scholars of
Ministry of Religious Affairs (CSS MoRA) UIN SyarifHidayatullah
Jakarta
2010 – 2012 Bendahara IBadanEksekutifMahasiswaJurusan (BEM-J)
KesehatanMasyarakat
2010 – 2011 Bendahara IPergerakanMahasiswa Islam Indonesia (PMII)
CabangCiputatKomisariatFakultasKedokterandanIlmuKesehatanKe
sehatanMasyarakat
2010 – 2011 SekretarisAsramaPutriPergerakanMahasiswa Islam Indonesia
CabangCiputat
2011 – 2012 SekretarisAsramaPutriPergerakanMahasiswa Islam Indonesia
CabangCiputat
2011 – 2012 BendaharaKorpPergerakanMahasiswa Islam Indonesia Putri
(KOPRI) CabangCiputat
2012 – 2013 KetuaKorpPergerakanMahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI)
CabangCiputat
2008 – Sekarang AnggotaCommunity of Santri Scholars of Ministry of Religious
Affairs (CSS MoRA)
ix
DAFTAR ISI
LEMBAR PERNYATAAN
LEMBAR PERSETUJUAN.......................................................................................... i
PENGESAHAN PANITIA UJIAN ............................................................................ ii
ABSTRAK .................................................................................................................. iii
KATA PENGANTAR ................................................................................................ iv
DAFTAR ISI ............................................................................................................... vi
DAFTAR TABEL ....................................................................................................... ix
DAFTAR GAMBAR ................................................................................................... x
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................................ x
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian ...................................................................................... 1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian ................................................................................. 6
1.3 Pertanyaan Penelitian ............................................................................................. 9
1.4 Tujuan Penelitian ................................................................................................... 9
1.4.1 Tujuan Umum .............................................................................................. 9
1.4.2 Tujuan Khusus ........................................................................................... 10
1.5 Manfaat Penelitian .............................................................................................. 11
1.5.1 Bagi Ibu Menyusui .................................................................................... 11
1.5.2 Bagi Peneliti .............................................................................................. 11
1.6 Ruang Lingkup Penelitian .................................................................................... 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Kelelahan Kerja .................................................................................................... 13
2.1.1 Pengertian Kelelahan Kerja ....................................................................... 13
2.1.2 Jenis Kelelahan Kerja ................................................................................ 15
2.1.3 Tanda Kelelahan Kerja .............................................................................. 17
2.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kelelahan Kerja .................. 17
2.1.5 Proses Terjadinya Kelelahan Kerja ........................................................... 40
x
2.1.6 Akibat Kelelahan Kerja ............................................................................ 43
2.1.7 Penanggulangan Kelelahan Kerja ............................................................. 45
2.1.8 Pengukuran Kelelahan Kerja ..................................................................... 45
2.2 Metode Penilaian Tingkat Risiko Ergonomi ........................................................ 54
2.2.1 QEC (Quick Expssure Checklist) .............................................................. 55
2.2.2 REBA (Rapid Body Assement) .................................................................. 57
2.2.3 RULA (Rapid Upper Limb Assement)....................................................... 58
2.2.3.1 Prosedur Penilaian Pengukuran RULA .............................................. 64
2.3 Menyusui .............................................................................................................. 76
2.3.1 Keuntungan Menyusui ............................................................................... 76
2.3.2 Frekuensi dan Lama Menyusui ................................................................. 77
2.3.3 Posisi dan Perlekatan Menyusui ................................................................ 78
2.3.4 Langkah-Langkah Menyusui yang Benar.................................................. 82
2.4 Kerangka Teori..................................................................................................... 84
BAB III KERANGKA KONSEP, DEFINISI OPERASIONAL, DAN
HIPOTESIS
3.1 Kerangka Konsep ................................................................................................. 86
3.2 Definisi Operasional............................................................................................. 89
3.3 Hipotesis ............................................................................................................... 92
BAB IV METODOLOGI PENELITIAN
4.1 Desain Penelitian .................................................................................................. 93
4.2 Waktu dan Tempat Penelitian .............................................................................. 93
4.3 Populasi dan Sampel ............................................................................................ 93
4.4 Metode Pengumpulan Data .................................................................................. 93
4.5 Instrumen Penelitian ............................................................................................ 45
4.6 Pengolahan Data................................................................................................. 106
4.7 Analisis Data ...................................................................................................... 107
xi
BAB VHASIL PENELITIAN
5.1 Analisis Univariat............................................................................................... 109
5.1.1 Gambaran Kelelahan pada Ibu Menyusui ≤ 6 Bulan di Kelurahan
Ciputat Timur Tahun 2013 ...................................................................... 109
5.1.2 Gambaran Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kelelahan
pada Ibu Menyusui ≤ 6 Bulan di Kelurahan Ciputat Timur 2013 ........... 111
5.2 Analisis Bivariat
5.2.1 Hubungan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kelelahan
pada Ibu Menyusui ≤ 6 Bulan di Kelurahan Ciputat Timur 2013 ........... 114
BAB VIPEMBAHASAN
6.1 Keterbatasan Penelitian ...................................................................................... 118
6.2 Gambaran Kelelahan pada Ibu Menyusui ≤ 6 Bulan di Kelurahan Ciputat
Timur 2013 ......................................................................................................... 118
6.3 Analisis Faktor Karakteristik Individu (Usia, Status Gizi,Aktivitas Fisik)pada
Ibu Menyusui ≤ 6 Bulan di Kelurahan Ciputat Timur 2013 .............................. 121
6.3.1 Hubungan antara Usia dengan Terjadinya Kelelahan ............................ 121
6.3.2 Hubungan antara Status Gizi dengan Terjadinya Kelelahan .................. 123
6.3.3 Hubungan antara Aktivitas Fisik dengan Terjadinya Kelelahan ............ 125
6.3.4 Hubungan antara Lama Menyusui dengan Terjadinya Kelelahan ......... 116
6.4 Analisis Faktor Karakteristik Pekerjaan (Risiko Ergonomi Postur Menyusui,
Lama Menyusui, Lingkungan Menyusui)pada Ibu Menyusui ≤ 6 Bulan di
Kelurahan Ciputat Timur 2013 .......................................................................... 127
6.4.1 Hubungan antara Risiko Ergonomi Postur Menyusuidengan Terjadinya
Kelelahan ................................................................................................ 127
6.4.2 Hubungan antara Lama Menyusuidengan Terjadinya Kelelahan .......... 131
6.4.3 Hubungan antara Kebisingan dengan Terjadinya Kelelahan ................. 134
6.4.4 Hubungan antara Pencahayaan dengan Terjadinya Kelelahan ............... 135
6.4.5 Hubungan antara Suhu dengan Terjadinya Kelelahan ........................... 136
xii
BAB VII SIMPULAN DAN SARAN
7.1 Simpulan ............................................................................................................ 138
7.2 Saran ................................................................................................................... 139
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
xiii
DAFTAR TABEL
2.1 Kategori Atas Ambang IMT untuk Indonesia………………………… ........... 23
2.2 Kerugian Berat Badan yang Kurang Ideal…………. .............................................. 23
2.3 Kelebihan dan Kekurangan Metode Pengukuran Kelelahan Kerja ......................... 52
2.4 Kelebihan dan Kekurangan Metode Pengukuran Risiko Ergonomi Postur Kerja ... 61
2.5 Skor Bagian Lengan Atas (Upper Limb)………………………………………… . 65
2.6 Skor Bagian Lengan Bawah …………………………………………… ............... 66
2.7 Skor Bagian Pergelangan Tangan …………………… ........................................... 67
2.8 Worksheet RULA………………………… ............................................................ 69
2.9 Skor Aktivitas ………………………… ................................................................. 69
2.10 Skor Beban………………………… ...................................................................... 70
2.11 Skor Bagian Leher …………………………………………… .............................. 71
2.12 Skor Bagian Batang Tubuh ………………………… ............................................. 72
2.13 Skor Bagian Kaki ………………………… ............................................................ 73
2.14 Skor Grup B Trunk Postur Score………………………… ..................................... 73
2.15 Skor Aktivitas………………………… .................................................................. 74
2.16 Skor Beban………………………… ...................................................................... 74
2.17 Grand Total Score ………………………… .......................................................... 75
2.18 Kategori Tindakan RULA………………………… ............................................... 75
3.1 Definisi Operasional………………………… ........................................................ 89
4.1 Skor Final RULA……………………………………..………………………… . 103
5.1 Gambaran Distribusi Kelelahan pada Ibu Menyususi ≤6 Bulan di Kelurahan
Pisangan Ciputat Timur Tahun 2013………………………… ............................. 109
5.2 Gambaran Distribusi Kelelahan pada Ibu Menyususi ≤6 Bulan di Kelurahan
Pisangan Ciputat Timur Tahun 2013………………………… ............................. 110
5.3 Gambaran Distribusi Responden Berdasarkan Faktor Kebiasaan Merokok pada
Ibu Menyususi ≤6 Bulan di Kelurahan Pisangan Ciputat Timur
Tahun2013……………………… ......................................................................... 111
Nomor Tabel Halaman
xiv
5.4 Gambaran Distribusi Responden Berdasarkan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Terjadinya Kelelahan pada Ibu Menyususi ≤6 Bulan di Kelurahan Pisangan
Ciputat Timur Tahun 2013………………………… ............................................ 112
5.5 Hubungan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kelelahan pada Ibu
Menyususi ≤6 Bulan di Kelurahan Pisangan Ciputat Timur Tahun
2013………………………… ............................................................................... 113
xv
DAFTAR GAMBAR
2.1 Range Pergerakan Lengan Atas ..................................................... 1165
2.2 Range Pergerakan Lengan Bawah ..................................................... 66
2.3 Range Pergerakan Pergelangan Tangan ............................................. 67
2.4 Range Pergerakan Pergelangan Tangan dengan Postur Alamiah ...... 68
2.5 Postur Tubuh Bagian Leher ............................................................... 71
2.6 Range Pergerakan Punggung ............................................................. 72
2.7 Range Pergerakan Kaki ...................................................................... 73
2.8 Posisi Cradle Hold ............................................................................. 81
2.9 Posisi Cross Cradle ............................................................................ 81
2.10 Posisi Football Hold .......................................................................... 81
Nomor Gambar Halaman
xvi
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Pernyataan Responden
Lampiran 2 : Kuesioner Penelitian
Lampiran 3 : Contoh Analisis RULA
Lampiran 4 : Output Olahan Analisis Univariat dan Bivariat
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Menurut WHO (1991) yang dikutip oleh Rohman (2012)ASI (Air Susu Ibu)
merupakan pemberian air susu kepada bayi yang langsung berasal dari kelenjar
payudara ibu. Kandungan ASI adalah emulsi lemak dalam larutan protein,
laktosa, dan garam-garam organik yang disekresi oleh kedua belah kelenjar
payudara ibu, yang berguna sebagai makanan yang utama bagibayi (Roesli,
2000).
Farrer (1999) menjelaskan manfaat pemberian ASI bagi bayi yaitu untuk
keamanan digesti bayi, ASI mengandung antibodi sehingga bayi yang mendapat
ASI umumnya jarang sakit dan jarang menderita alergi jika dibandingkan dengan
bayi yang mendapatkan susu formula, dan bayi yang disusui sendiri akan
memperoleh kesempatan didekap ibunya. Bagi ibu selain memberikan manfaat
fisik dengan membantu involusi uterus, mengurangi insiden kanker payudara,
menghemat waktu dan uang juga memberikan kepuasan emosional dengan
timbulnya persaan berhasil dalam pemenuhan tugas sebagai ibu.
Besarnyamanfaat ASI bagi bayi kemudian memunculkan program ASI
eksklusif. Di Indonesia, pemerintah telah menetapkan program pemberian ASI
eksklusif. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI
Eksklusif dijelaskan bahwa ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada
2
bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau
mengganti dengan makanan atau minuman lain. Sehingga menyusui menjadi
suatu aktivitas rutin ibu setelah melahirkan. Kemudian dalam Keputusan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 450/MENKES/SK/IV/2004 tentang
Pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara Eksklusif pada Bayi di Indonesia.
Menurut Soejono (1985), menyusui merupakan pekerjaan biologik yang
mulia bagi semua jenis mamalia dan sebagai satu kesatuan dari fungsi
reproduksi. nutrisi pada bayi Menurut Health (2000) dalam Suryani (2012)
menyusui merupakan keterampilan yang dipelajari ibu dan bayi, dimana
keduanya membutuhkan waktu dan kesabaran untuk pemenuhan selama enam
bulan. Sehingga, menyusui merupakan kegiatan yang dilakukan selama berjam-
jam dan berkali-kali setiap harinya oleh ibu pasca melahirkan. Menurut U.S.
Departement of Health and Human Services Office on Woman’s Health (2006)
disebutkan bahwa menyusui dilakukan minimal 2 jam sekali, namun waktu
menyusui ini tidak boleh dijadwal secara ketat karena semakin sering bayi
menyusu, maka akan menstimulasi payudara ibu untuk memproduksi lebih
banyak ASI.
Setiap ibu yang menyusui harus berada pada posisi yang tepat dan dalam
kondisi nyaman karena hal ini akan mempengaruhi proses laktasi (Roesli, 2009).
Hal ini diperkuat dengan pernyataan Soetjiningsih (1997) bahwa posisi
menyususi yang tidak benar dapat mengakibatkan puting susu menjadi lecet
sehingga ibu enggan untuk menyusui yang dapat berakibat produksi ASI
3
menurun dan bayi tidak puas menyusu. Selama kegiatan menyusui berlangsung,
ibu dipaksa untuk memposisikan diri dan bayi secara tepat agar proses menyusui
dapat berjalan lancar. Salah satu faktor yang mempengaruhi terhambatnya
menyusui adalah kurangnya bantuan agar posisi bayi terasa nyaman membuat
menyusui kurang menyenangkan (Welford, 2008:1 dalam Gunawan, 2012). Satu
gejala yang sering dilaporkan ibu yang baru pertama kali menyusui bayinya yang
membuat ibu memperpendek lamanya dalam menyusui adalah kelelahan
(fatigue) (Chapman,1998 dalam Rohman, 2012). Kelelahan yang dirasakan oleh
ibu-ibu selama menyusui menurunkan produksi ASI selama bulan pertama
postpartum dan menjadi faktor yang utama untuk menyapih bayinya (Rohman,
2012).
Kelelahan dapat mengganggu menyusui, sehingga intervensi
meminimalkan kelelahan adalah penting (Miligan A.R, Flenniken M.P & Pugh
C.L, 1996). Upaya untuk meminimalkan kelelahan ibu selama menyusui adalah
penelitian tentang “Positioning intervensi to minimize fatigue in breastfeeding
women“ (Miligan A.R, Flenniken M.P & Pugh C.L, 1996) yaitu dimana posisi
yang dipilih adalah posisi yang dapat memberikan ibu istirahat dan sedikit
mengeluarkan energi. Posisi yang paling banyak digunakan ibu saat menyusui
terutama pada masa-masa awal menyusui adalah posisi duduk berupa posisi
cradle hold, cross cradle, dan football hold(Widodo, 2011).Walaupun banyak
posisi menyusui yang telah menjadi standard keperawatan sebagai based
4
practice, namun posisi tersebut masih perlu divalidasi yang dapat menurunkan
kelelahan (Rohman, 2012).
Posisi ibu selama menyusui menentukan bagaimana postur tubuh ibu
selama kegiatan menyusui berlangsung. Edy dan Samad (2011) menyebutkan
bahwa postur tubuh merupakan salah satu dari hal yang paling sering
dihubungkan dengan faktor risiko ergonomi. Suryana (2001) dalam Rahmawati
dan Sugiharto (2011) menyatakan bahwa seorang pekerja bila bekerja tidak pada
posisi ergonomis, maka akan cepat merasa lelah, sering mengeluh sakit leher,
sakit pinggang, rasa semutan, pegal-pegal di lengan dan tungkai serta gangguan
kesehatan lainnya.
Ergonomi adalah ilmu tentang kerja, dimana mempertimbangkan faktor
manusia sebagai pelaku pekerjaan, bagaimana cara melakukan pekerjaan
tersebut, peralatan yang digunakan, tempat dilakukannya pekerjaan, dan aspek
psikososial dari situasi pekerjaan (Pheasant, 2003). Menurut Occupational Safety
and Health Administration (OSHA), ergonomi adalah ilmu yang mempelajari
tentang bagaimana menyesuaikan kondisi tempat kerja dan tuntutan pekerjaan
dengan kemampuan pekerja.
Menurut Suma’mur (1996) salah satu faktor yang berpengaruh terhadap
kesehatan kerja adalah yang berhubungan dengan ergonomi yaitu sikap dan cara
kerja (postur tubuh), kegelisahan kerja, beban kerja yang tidak adekuat,
monotonnya pekerjaan, jam kerjayang tidak sesuai, dan kerja yang berulang-
ulang. Pengaruh-pengaruh tersebut terkumpul di tubuh dan mengakibatkan
5
perasaan lelah. Menurut Siswanto (1999) dalam Mauludi (2010) bahwasanya
faktor penyebab kelelahan kerja adalah pengorganisasian kerja, faktor psikologis,
lingkungan kerja, status kesehatan dan status gizi. Sedangkan pendapat lain
mengatakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kelelahan adalah
kesegaran jasmani, kebiasaan merokok, masalah psikologis, status kesehatan,
jenis kelamin, status gizi, waktu kerja, beban kerja, usia, dan masalah lingkungan
kerja (Tarwaka dkk, 2004). Dalam penelitian Oentoro (2004) menunjukkan
bahwa faktor individu seperti umur, pendidikan, masa kerja, status perkawinan
dan status gizi mempunyai hubungan terhadap terjadinya kelelahan kerja.
Menurut Pearl Medic (2011) aktivitas fisik yang berlebihan merupakan salah
satu faktor terjadinya kelelahan. Hasil penelitian yang dilakukan Miligan A.R,
Flenniken M.P & Pugh C.L, (1996) salah satu faktor yang menyebabkan
terjadinya kelelahan pada ibu menyusui yaitu postur menyusui yang digunakan.
Pada ibu menyusui, kelelahan dapat mempengaruhi aktivitas proses
pemberian ASI. Jika ibu sering mengalami kelelahan, selain akan mengganggu
aktivitas pemberian ASI, juga akan memunculkan risiko terjadinya kesakitan
pada ibu atau berkembang menjadi MSDs karena aktivitas menyusui dilakukan
ibu berulang-ulang setiap hari.
Munculnya kelelahan pada saat menyusui diperkirakan disebabkan
karena prinsip ergonomi belum diterapkan dalam kegiatan menyusui yang
dilakukan oleh ibu menyusui pada umumnya, padahal menyusui merupakan
6
kegiatan sehari-hari ibu yang baru melahirkan. Sehingga masalah yang
kemudian muncul adalah kelelahan ibu selama kegiatan menyusui berlangsung
sebagai akibat dari posisi menyusui ibu yang bertahan selama 20-30 menit
berkali-kali setiap hari. Hal ini diperkuat dengan hasil studi pendahuluan yang
dilakukan pada bulan Januari terhadap 10 ibu menyusui di Kelurahan Pisangan.
Adapun berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada 10 ibu
menyusui ≤ 6 bulan diketahui rata-rata ibu menyusui mengalami kelelahan
ringan 80% dan kelelahan menengah 20% artinya, dari 10 orang yang
diwawancarai diketahui seluruh ibu menyusui mengalami kelelahan dalam
meyusui. Meskipun tingkat kelelahannya berbeda-beda namun jika terjadi
secara berulang-ulang berakibat kepada kelelahan kronis yang mampu
mempengaruhi pengurangan kapasitas kerja dan ketahanan tubuh dan jika
dipaksakan terus menerus kelelahan akan bertambah dan sangat menganggu
hingga menyebabkan kelelahan klinis yang berdampak pada peningkatan angka
sakit (Suma’mur, 1986).
Berdasarkan studi pendahuluan tersebut, maka peneliti ingin mengetahui
faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kelelahan pada ibu menyusui ≤ 6
bulan di Kelurahan Pisangan Ciputat Timur 2013. Penelitian ini merupakan
penelitian di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diterpkan
pada aktivitas menyusui. Aktivitas menyusui merupakan pekerjaan rutin yang
dilakukan ibu-ibu pasca melahirkan pada umumnya. Perlunya penerapan K3
7
terutama aspek ergonomi pada aktivitas menyusui bertujuan untuk
meminimalisir risiko-risiko ergonomi pada ibu menyusui, terutama terkait
kelelahan posisi duduk ibu saat menyusui. Dengan adanya penelitian ini,
menunjukkan bahwa K3 dapat diterapkan dimana saja, dimana terdapat
aktivitas. Aktivitas yang diteliti di sini adalah aktivitas menyusui. Pada aktivitas
menyusui ini, K3 perlu diterapkan terutama kaitannya dengan aspek ergonomi.
Dengan demikian, maka risiko-risiko ergonomi pada ibu menyusui dapat
diminimalisir, terutama terjadinya kelelahan posisi duduk ibu saat menyusui.
Dengan adanya penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk
memperbaiki posisi duduk ibu saat menyusui yang lebih ergonomis dimana
posisi ini yang paling banyak digunakan ibu saat menyusui sehingga dapat
membantu meningkatkan kelancaran pemberian ASI di Kelurahan Pisangan
Ciputat Timur
1.2 Rumusan Masalah
Menurut Health (2000) dalam Suryani (2012) menyusui merupakan
keterampilan yang dipelajari ibu dan bayi, dimana keduanya membutuhkan waktu
dan kesabaran untuk pemenuhan selama enam bulan. Sehingga,menyusui
merupakan kegiatan yang dilakukan selama berjam-jam dan berkali-kali setiap
harinya oleh ibu pasca melahirkan. Agar proses menyusui berjalan dengan lancar,
maka seorang ibu harus mempunyai keterampilan menyusui agar ASI dapat
mengalir dari payudara ibu ke bayi secara efektif. Keterampilan menyusui yang
8
baik meliputi postur menyusui dan perlekatan bayi pada payudara yang tepat. Edy
dan Samad (2011) menyebutkan bahwa postur tubuh merupakan salah satu dari
hal yang paling sering dihubungkan dengan faktor risiko ergonomi. Posisi yang
nyaman untuk menyusui sangat penting agar proses menyusui berjalan lancar.
Satu gejala yang sering dilaporkan ibu yang baru pertama kali menyusui bayinya
yang membuat ibu memperpendek lamanya dalam menyusui adalah kelelahan
(fatigue) (Chapman,1998 dalam Rohman, 2012). Prinsip ergonomi secara umum
belum diterapkan pada aktivitas menyusui, sehingga masalah yang kemudian
terjadi adalah kelelahanibu selama kegiatan menyusui berlangsung dan ini akan
mengganggu proses menyusui maupun proses laktasi.
Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan diketahui dari 10 ibu menyusui
≤ 6 bulan yang diwawancarai di Kelurahan Pisangan Ciputat Timur, diketahui
rata-rata seluruh ibu menyusui mengalami kelelahan saat meyusui. Kelelahan
(fatigue) merupakan satu gejala yang sering dilaporkan ibu yang baru pertama
kali menyusui bayinya yang membuat ibu memperpendek lamanya dalam
menyusui. Diperkirakan faktor pencetus terjadinya kelelahan dapat berasal dari
risiko ergonomi postur menyusui, usia, kebiasaan merokok, status gizi, aktivitas
fisik,lama menyusui, lingkungan kerja dan lingkungan kerja. Dengan demikian
diperlukan adanya suatu penelitian tentang faktor-faktor yang
berhubungandengan terjadinya kelelahan pada ibu menyusui ≤ 6 bulan di
Kelurahan Pisangan Ciputat Timur 2013.
9
1.3 Pertanyaan Penelitian
1. Bagaimana gambaran kelelahan pada ibu menyusui ≤ 6 bulan di Kelurahan
Pisangan Ciputat Timur 2013?
2. Bagaimana gambaran faktor karakteristik individu(usia, kebiasaan merokok,
status gizi, aktivitasfisik) pada ibu menyusui ≤ 6 bulan di Kelurahan
Pisangan Ciputat Timur 2013?
3. Bagaimana gambaran faktor karakteristik pekerjaan (risiko ergonomi postur
menyusui, lama menyusui dan lingkungan menyusui) pada ibu menyusui ≤ 6
bulan di Kelurahan Pisangan Ciputat Timur 2013?
4. Apakah ada hubungan antara faktor karakteristik individu (usia, kebiasaan
merokok, status gizi, aktivitas fisik) dengan kelelahan pada ibu menyusui ≤ 6
bulan di Kelurahan Pisangan Ciputat Timur 2013?
5. Apakah ada hubungan antara faktor karakteristik pekerjaan (risiko ergonomi
postur menyusui, lama menyusui dan lingkungan menyusui) dengan
kelelahan pada ibu menyusui ≤ 6 bulan di Kelurahan Pisangan Ciputat
Timur 2013?
1.4 Tujuan Penelitian
1.4.1 Tujuan Umum
Diketahuinya faktor-faktor yang berhubungan dengan terjadinya
kelelahan pada ibu menyusui ≤ 6 bulan di Kelurahan Pisangan Ciputat
Timur 2013.
10
1.4.2 Tujuan Khusus
1. Diketahuinya gambaran kelelahan pada ibu menyusui ≤ 6 bulan di
Kelurahan Pisangan Ciputat Timur 2013.
2. Diketahuinyagambaran faktor karakteristik individu (usia, kebiasaan
merokok, status gizi, aktivitasfisik) pada ibu menyusui ≤ 6 bulan di
Kelurahan Pisangan Ciputat Timur 2013.
3. Diketahuinyagambaran faktor karakteristik pekerjaan (risiko ergonomi
postur menyusui, lama menyusui dan lingkungan menyusui) pada ibu
menyusui ≤ 6 bulan di Kelurahan Pisangan Ciputat Timur 2013.
4. Diketahuinya hubungan antara faktor karakteristik individu (usia,
kebiasaan merokok, status gizi, aktivitas fisik) dengan kelelahan pada
ibu menyusui ≤ 6 bulan di Kelurahan Pisangan Ciputat Timur 2013.
5. Diketahuinya hubungan antara faktor karakteristik pekerjaan (risiko
ergonomi postur menyusui, lama menyusui dan lingkungan menyusui)
dengan kelelahan pada ibu menyusui ≤ 6 bulan di Kelurahan Pisangan
Ciputat Timur 2013.
11
1.5 Manfaat Penelitian
1.5.1 Bagi IbuMenyusui
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi bagi para ibu
menyusui maupun calon ibu menyusui mengenai faktor-faktor yang
berhubungan denganterjadinya kelelahan sehingga dapat melakukan
upaya-upaya untuk mengurangi aspek kelelahan pada saat menyusui.
1.5.2 Bagi Peneliti
1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti lain yang akan
melakukan penelitian terkait kejadian kelelahan.
2. Dapat mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan terkait risiko ergonomi
yang telah didapatkan di perkuliahan pada tempat kerja yang
sesungguhnya.
3. Melatih pola pikir sistematis dalam menghadapi masalah-masalah
khusunya dalam bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
1.6 Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan oleh mahasiswa peminatan Kesehatan dan
Keselamatan Kerja Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negri
Syarif Hidayatullah Jakarat yang dilakukan pada bulan Juni 2012 sampai Juli
2013. Adapun lokasinya di Kelurahan Pisangan Ciputat Timur. Penelitian ini
merupakan salah satu garapan bidang K3 (Kesehatan Keselamatan Kerja) yang
bertujuan mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan terjadinya
12
kelelahan pada ibu menyusui ≤6 bulan di Kelurahan Pisangan Ciputat Timur
2013.
Penelitian ini bersifat kuantitaif dengan menggunakan desain studi cross
sectional dimana peneliti menggunakan data primer dan sekunder. Data primer
yaitu peneliti melakukan observasi langsung pada saat ibu menyusi, untuk melihat
potensi risiko terjadinya kelelahan dengan kriteria penilaian postur berdasarkan
metode Rapid Upper Limb Assessment (RULA) yaitu dengan pengukuran
langsung serta menggunakan kuesioner kepada ibu yang sedang menyusui ≤ 6
bulan untuk mengetahui variabel faktor krakteristik individu dan pekerjaan.
Sedangkan data sekunder yaitu data ibu menyusui dibawah sama dengan enam
bulan diperoleh dari posyandu dengan cara telaah dokumen.
13
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Kelelahan Kerja
2.1.1 Pengertian Kelelahan Kerja
Kelelahan dapat diartikan sebagai suatu kondisi menurunnya
efisiensi, performa kerja dan berkurangnya kekuatan atau ketahanan
fisik tubuh untuk terus melanjutkan kegiatan yang harus dilakukan
(Wingnjosoebroto, 2003 dalam Virgy, 2011). Kelelahan adalah suatu
mekanisme perlindungan tubuh agar tubuh menghindari kerusakan lebih
lanjut, sehingga dengan demikian terjadilah pemulihan (Suma’mur,
1989). Rizeddin (2000) dalam Nurhidayati (2009) menyatakan kelelahan
menurunkan kapasitas kerja dan ketahanan kerja yang ditandai oleh
sensasi lelah, motivasi menurun, aktivitas menurun. Menurut Grandjean
(1997) dalam Virgy (2011) kelelahan kerja merupakan gejala yang
ditandai adanya perasaan lelah dan kita akan merasa segan dan aktifitas
akan melemah serta ketidakseimbangan. Selain itu, keinginan untuk
berusaha melakukan kegiatan fisik dan mental akan berkurang karena
disertai perasaan berat, pening, capek. Istilah kelelahan menunjukkan
kondisi yang berbeda-beda dari setiap individu, tetapi semuanya
bermuara pada kehilangan efisiensi dan penurunan kapasitas kerja serta
ketahanan tubuh (Tarwaka et al,2004).
14
Menurut Cameron (1973) yang dikutip oleh Rahmawati (1998)
kelelahan kerja merupakan kriteria yang kompleks yang tidak hanya
menyangkut kelelahan fisiologis dan psikologis tetapi dominan
hubungannya dengan penurunan kinerja fisik, adanya perasaan lelah,
penurunan motivasi dan penurunan produktivitas kerja. Gambaran
mengenai gejala kelelahan (fatigue symptoms) secara subjektif dan
obyektif antara lain;
a. Perasaan lesu, ngantuk dan pusing
b. Kurang mampu berkonsentrasi
c. Berkurangnya tingkat kewaspadaan
d. Persepsi yang buruk dan lambat
e. Berkurangnya gairah untuk bekerja
f. Menurunnya kinerja jasmani dan rohani (Budiono dkk, 2003).
Beberapa gejala tersebut dapat menyebabkan penurunan efisiensi
dan efektivitas kerja fisik dan mental. Sejumlah gejala tersebut
manifestasinya timbul berupa keluhan oleh tenaga kerja dan seringnya
tenaga kerja tidak masuk kerja (Budiono dkk, 2003).
Kelelahan adalah aneka keadaan yang disertai penurunan efisiensi
dan ketahan dalam bekerja, yang dapat dosebabkan oleh :
a. Kelelahan sumber utamanya adalah mata (kelelahan visual).
b. Kelelahan fisik umum.
c. Kelelahan syaraf.
15
d. Kelelahan oleh lingkungan yang monoton.
e. Kelelahan oleh lingkungan kronis terus menerus sebagai faktor
secara menetap (Suma’mur, 1999).
Suma’mur (1996) menyatakan bahwa poduktifitas mulai
menurun setelah empat jam bekerja terus menerus (apapun jenis
pekerjaannya) yang disebabkan oleh menurunnya kadar gula didalam
darah. Itulah sebabnya istirahat sangat diperlukan minimal setengah jam
setelah empat jam bekerja terus menerus agar pekerja memperoleh
kesempatan untuk makan dan menambah energi yang diperlukan tubuh
untuk bekerja. Manuaba (1990) dalam Virgy (2011) menjelaskan bahwa
jam kerja berlebihan, jam kerja lembur diluar batas kemampuan akan
mempercepat timbulnya kelelahan, menurunkan ketepatan dan ketelitian.
Oleh karena itu setiap fungsi tubuh memerlukan keseimbangan yang
ritmis antara asupan energi dan pengganti energi (kerja-istirahat), maka
diperlukan adanya waktu istirahat pendek (15 menit setelah 1,5-2 jam
kerja) untuk mempertahankan efisiensi dan performa kerja (Virgy, 2011).
2.1.2 Jenis Kelelahan Kerja
Jenis kelelahan meliputi atas dua bagian:
a. Kelelahan Otot (Muscular Fatigue)
Kelelahan otot menurut Suma’mur (1999) adalah tremor pada
otot atau perasaan nyeri yang terdapat pada otot. Hasil percobaan yang
dilakukan para peneliti pada otot mamalia, menunjukkan kinerja otot
16
berkurang dengan meningkatnya ketegangan otot sehingga stimulasi
tidak lagi menghasilkan respon tertentu. Fenomena berkurangnya
kinerja otot setelah terjadinya tekanan melalui fisik untuk suatu waktu
tertentu disebut kelelahan otot secara fisiologis, dan gejala yang
ditunjukkan tidak hanya berupa berkurangnya tekanan fisik namun
juga pada makin rendahnya gerakan.
b. Kelelahan Umum
Pendapat Grandjean (1993) yang dikutip oleh Tarwaka, dkk
(2004), biasanya kelelahan umum ditandai dengan berkurangnya
kemauan untuk bekerja, yang sebabnya adalah pekerjaan yang
monoton, intensitas dan lamanya kerja fisik, keadaan lingkungan,
Sebab-sebab mental, status kesehatan dan keadaan gizi. Secara umum
gejala kelelahan dapat dimulai dari yang sangat ringan sampai
perasaan yang sangat melelahkan. Kelelahan subjektif biasanya terjadi
pada akhir jam kerja, apabila beban kerja melebihi 30-40% dari tenaga
aerobik. Pengaruh-pengaruh ini seperti berkumpul didalam tubuh dan
mengakibatkan perasaan lelah (Suma’mur, 1996). Menurut Budiono
(2003), gejala umum kelelahan adalah suatu perasaan letih yang luar
biasa dan terasa aneh. Semua aktivitas menjadi terganggu dan
terhambat karena munculnya gejala kelelahan terebut. Tidak adanya
gairah untuk bekerja baik secara fisik maupun psikis, segalanya terasa
berat dan merasa mengantuk.
17
2.1.3 Tanda Kelelahan Kerja
Pada umumnya orang lelah menunjukkan tanda-tanda sebagai berikut ;
a. Penurunan perhatian
b. Perlambatan dan hambatan persepsi
c. Lamban dan sukar berfikir
d. Penurunan kemampuan atau dorongan untuk bekerja
e. Kurangnya efisiensi kegiatan-kegiatan fisik dan mental
Jika menderita lelah berat secara terus menerus maka akan
mengakibatkan kelelahan kronis dengan gejala lelah sebelum bekerja. Jika
terus berlanjut dan menimbulkan sakit kepala, pusing, mual dan sebagainya
maka kelelahan itu dinamakan lelah klinis yang akan mengakibatkan malas
bekerja (Sedarmayanti 1996).
2.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kelelahan Kerja
a. Postur Kerja
Postur tubuh dapat didefinisikan sebagai orientasi reaktif dari
bagian tubuh terhadap ruang. Untuk melakukan orientasi tubuh tersebut
selama beberapa rentang waktu dibutuhkan kerja otot untuk menyangga
atau menggerakkan tubuh. Postur yang diadopsi manusia saat melakukan
beberapa pekerjaan adalah hubungan antara dimensi tubuh sang pekerja
dengan dimensi beberapa benda dalam lingkungan kerjanya (Phesant,
1991).
18
Postur tubuh dalam kerja sangat ditentukan oleh jenis pekerjaan
yang dilakukan, masing-masing posisi kerja mempunyai pengaruh yang
berbeda-beda terhadap tubuh. Pada pekerjaan yang dilakukan dengan
posisi duduk seperti halnya para ibu menyusui hanya menggunakan
bantal sebagai penompang cara kerjanya, tempat duduk yang dipakai
harus memungkinkan untuk melakukan variasi perubahan posisi, kursi
yang baik adalah kursi yang mengikuti lekuk punggung, siburan dan
tingginya dapat diatur (Setyawati,2001).
Posisi dalam bekerja sangat ditentukan oleh jenis pekerjaan yang
dilakukan, masing-masing posisi kerja mempunyai pengaruh yang
berbeda-beda terhadap tubuh. Menurut Soeripto (1989), perencanaan dan
penyesuaian alat yang tepat bagi tenaga kerja dapat meningkatkan
produktivitas, menciptakan keselamatan dan kesehatan kerja serta
kelestarian lingkungan kerja, dan juga memperbaiki kualitas produk dari
suatu proses produksi. Posisi dalam bekerja memiliki hubungan yang
positif dengan timbulnya kelelahan kerja. Tidak peduli apakah pekerja
harus berdiri, duduk atau dalam sikap posisi kerja yang lain,
pertimbangan-pertimbangan ergonomis yang berkaitan dengan
sikap/posisi kerja akan sangat panting. Beberapa jenis pekerjaan akan
memerlukan sikap dan posisi tertentu yang kadang-kadang cenderung
untuk tidak mengenakkan. Kondisi kerja seperti ini memaksa pekerja
selalu berada pada sikap dan posisi kerja yang tidak nyaman dan kadang-
19
kadang juga harus berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Hal ini
tentu saja akan mengakibatkan pekerja cepat lelah, membuat banyak
kesalahan atau menderita cacat tubuh.
Sikap tubuh dalam bekerja harus memperhatikan :
1) Agar senantiasa diupayakan agar semua pekerjaan dilaksanakan
dengan sikap duduk dan sikap berdiri secara bergantian.
2) Segala posisi dan sikap tubuh yang tidak alami dihindarkan atau
diusahakan agar beban statis sekecil-kecilnya.
Menurut Grandjean (1988: 167) sifat pekerjaan yang monoton
(kurang bervariasi) merupakan salah satu faktor penyebab kelelahan
kerja. Waters dan Bhattacharya (1996) yang dikutip oleh Tarwaka dkk,
(2004) berpendapat agak lain, bahwa kontraksi otot baik statis maupun
dinamis dapat meyebabkan kelelahan otot setempat. Kelelahan tersebut
terjadi pada waktu ketahanan (Endurance time) otot terlampaui. Waktu
ketahanan otot tergantung pada jumlah tenaga yang dikembangkan oleh
otot sebagai suatu prosentase tenaga maksimum yang dapat dicapai oleh
otot. Kemudian pada saat kebutuhan metabolisme dinamis dan aktivitas
melampaui kapasitas energi yang dihasilkan oleh tenaga kerja, maka
kontraksi otot akan terpengaruh sehingga kelelahan seluruh badan terjadi.
b. Usia
Menurut Setyawati (1994) yang dikutip oleh Silastuti (2006)
faktor individu seperti umur juga dapat berpengaruh terhadap waktu
20
reaksi dan perasaan lelah tenaga kerja. Pada umur yang lebih tua terjadi
penurunan kekuatan otot, tetapi keadaan ini diimbangi dengan stabilitas
emosi yang lebih baik dibanding tenaga kerja yang berumur muda yang
dapat berakibat positif dalam melakukan pekerjaan. Menurut Hidayat
2003 dalam Mauludi 2010 mendapatkan bukti di Negara Jepang
menunjukkan bahwa pekerja yang berusia 40-50 tahun akan lebih cepat
menderita kekelahan kerja dibandingkan dengan pekerja relative lebih
muda. Dengan menanjaknya umur maka kemampuan jasmani dan
rohanipun akan menurun secara perlahan-lahan. Menurut Akerstedt et al
(2002) dalam Dewi (2006) bahwa kelelahan lebih cenderung terjadi pada
pekerja berumur kurang lebih sama dengan 49 tahun. Pada penelitian
Dewi (2006) diketahui bahwa responden yang paling banyak mengalami
kelelahan adalah pekerja yang berusia 25-35 tahun yaitu sebnyaka 26
orang (55,3%), pada penelitian ini didapatkan P-value 0,180 yang
menyatakan tidak adanya hubungan antara usia pekerjaan dengan
kelelahan kerja. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh J Hum lact
University of Kansas School of Nursing, Kansas City 66160-7502,
Amerika Serikat (1998) bahwa usia ibu berkorelasi positif dengan
kelelahan (r = 0,31-0,50, p <.05).
c. Kebiasaan Merokok
Menurut Mauludi (2010) semakin lama dan tingginya frekuensi
merokok, semakin tinggi pula tingkat keluhan otot yang dirasakan. Hal ini
21
sebenarnya terkait erat dengan kondisi kesegaran tubuh seseorang.
Kebiasaan merokok akan dapat menurunkan kapasitas paru–paru,
sehingga kemampuan untuk mengkonsumsi oksigen menurun dan sebagai
akibatnya tingkat kesegaran juga menurun. Apabila yang bersangkutan
harus melakukan tugas yang menuntut pengerahan tenaga, maka akan
mudah lelah karena kandungan oksigen dalam darah rendah, pembakaran
karbohidrat terhambat, terjadi tumpukan asam laktat dan akhirnya timbul
kelelahan (Tarwaka dkk, 2004). Seseorang dapat diakatan perokok ringan
apabila merokok kurang dari 10 batang perhari, dikatakan perokok sedang
apabila merokok 10-20 batang perhari dan dikatakan perokok berat
apabila merokok lebih dari 20 batang perhari (Bustan, 2000). Penentuan
derajat merokok dengan Indeks Brinkman (IB), yaitu perkalian jumlah
rata-rata batang rokok dihisap sahari dikalikan lama merokok dalam
tahun. Interpretasi hasilnya adalah derajat ringan (0-200), sedang (200-
600), dan berat (>600) (PDPI, 2001 dalam Nugraha, 2010).
d. Status Gizi
Status gizi merupakan salah satu unsur yang menentukan kualitas
fisik dan kondisi fisik tenaga kerja sehingga berpengaruh terhadap
terjadinya kelelahan (Wignjosoebroto, 2003 dalam Virgy, 2011). Tubuh
memerlukan zat-zat dari makanan untuk pemeliharaan tubuh, perbaikan
kerusakan sel dan jaringan. Zat makanan tersebut diperlukan juga untuk
bekerja dan meningkat sepadan dengan lebih beratnya pekerjaan
22
(Suma’mur, 1996). Tingkat gizi, terutama bagi pekerja kasar dan berat
adalah faktor penentu derajat produktivitas kerjanya. Beban kerja yang
terlalu berat sering disertai penurunan berat badan (Suma’mur, 1996).
Status gizi ini bisa dihitung salah satunya adalah dengan
menghitung IMT dengan rumus:
Untuk mengetahui status gizi seseorang maka ada kategori
ambang batas IMT yang digunakan, seperti yang terlihat pada tabel 2.1
dibawah ini yang merupakan ambang IMT untuk Indonesia.
Tabel 2.1.
Kategori Atas Ambang IMT untuk Indonesia
Kategori IMT (Kg/M2)
Kurus Kekurangan berat badan tingkat berat <17,0
Kekurangan berat badan tingkat ringan 17,1-18,4
Normal 18,5-25,0
Gemuk Kelebihan berat badan tingkat ringan 25,1-27,0
Kelebihan berat badan tingkat bera ≥ 27,0
Sumber: Depkes, 2003
Menurut Pekik (2006) dalam Kasanah (2011) menyatakan bahwa
Indeks Masa Tubuh (IMT) mempunyai beberapa kelebihan yaitu
pengukuran sederhana dan mudah serta menentukan kelebihan dan
kekurangan berat badan. Indeks Masa Tubuh (IMT) ini tidak lepas dari
kekurangan yaitu hanya dapat digunakan untuk menentukan status gizi
orang dewasa (usia 18 tahun keatas).
Berat badan (kg)
IMT =
Tinggi badan (m) x Tinggi badan (m)
23
Tabel 2.2
Kerugian Berat Badan yang Kurang Ideal
Berat Badan Kerugian
Kurang (kurus) Penampilan cenderung kurang baik, mudah lelah, risiko
penyakit tinggi, wanita kurus yang hamil mempunyai risiko
tinggi melahirkan bayi dengan BBLR, kurang mampu bekerja
keras.
Kelebihan
(gemuk)
Penampilan kurang menarik, gerakan tidak gesit dan lamban,
risiko penyakit jantung, pada wanita dapat menyebabkan
gangguan haid.
Sumber: 1 Dewa Nyoman Supariasa, dkk., (2002:61) dalam Nurhidayati (2009)
Berat badan yang kurang ideal baik itu kurang ataupun kelebihan
dapat menimbulkan kerugian. Masalah kekurangan atau kelebihan gizi
pada orang dewasa (usia 18 tahun ke atas) merupakan masalah penting,
karena selain mempunyai risiko penyakit tertentu, juga dapat
mempengaruhi produktivitas kerja. Akibat kekurangan zat gizi, maka
simpanan zat gizi pada tubuh akan digunakan untuk memenuhi
kebutuhan. Bila hal ini berlangsung lama, maka simpanan zat gizi akan
habis dan terjadi kemerosotan jaringan, dengan meningkatnya defisiensi
zat gizi maka muncul perubahan biokimia dan rendahnya zat–zat gizi
dalam darah, berupa rendahnya tingkat Hb, serum vitamin A dan karoten.
Dapat pula terjadi peningkatan beberapa hasil metabolisme seperti asam
laktat dan piruvat pada kekurangan tiamin. Bila keadaan ini berlangsung
lama, akan mengakibatkan terjadinya perubahan fungsi tubuh yang tanda-
tandanya, yaitu kelemahan, pusing, kelelahan, nafas pendek dan lain-lain
24
(Supariasa dkk., 200 dalam Mauludi, 2010). Sedangkan untuk orang yang
mempunyai kelebihan berat badan (gemuk) juga akan mudah mengalami
kelelahan karena, orang yang gemuk membutuhkan jumlah energi yang
lebih besar untuk membawa tubuhnya, seiring dengan kenaikan berat
badannya. (Almatsier 2004 )
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Eraliesa (2008)
dalam Mauludi (2010) terdapat hubungan antara status gizi dengan
tingkat kelelahan, dengan nilai P-valuenya 0,002. Hasil riset
menunjukkan bahwa secara klinis terdapat hubungan antara status gizi
seseorang dengan performa tubuh secara keseluruhan, orang yang berada
dalam kondisi gizi yang kurang baik dalam arti intake makanan dalam
tubuh kurang dari normal maka akan lebih mudah mengalami kelelahan
dalam melakukan pekerjaan (Oentoro, 2004).
e. Status Pernikahan
Status pernikahan menurut Konsey (1965) dalam Mauludi (2010),
membagi status pernikahan dalam tiga kelompok yaitu single, married,
dan post married. Kelompok single adalah kelompok yang tidak menikah
atau belum menikah. Kelompok married adalah kelompok yang sedang
berada dalam status pernikahan yang sah secara hukum, sedangkan
kelompok pos married adalah kelompok yang sudah pernah menikah
tetapi kemudian berpisah karena perceraian atau kematian. Pernikahan
menyebabkan meningkatnya tanggung jawab yang dapat membuat
25
pekerjaan tetap lebih berharga dan penting. Tugas-tugas perkembangan
yang dimiliki oleh orang yang sudah menikah menurut Sudirman (1987)
dalam Mauludi (2010):
1) Belajar hidup dengan pasangan dalam perkawinan.
2) Mulai hidup berkeluarga
3) Memelihara anak
4) Mengatur rumah tangga
5) Memulai dalam pekerjaan.
Seseorang yang sudah menikah dan memiliki keluarga maka akan
mengalami kelelahan akibat kerja dan setelah dirumah harus melyani
anak dan istrinya yang mana waktu tersebut digunakan untuk beristirahat
(Irma, 2009 dalam Mauludi, 2010). Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan oleh Eraliesa (2008) dalam Mauludi (2010) terdapat hubungan
antara status perkawinan dengan tingkat kelelahan, dengan nilai P-
valuenya 0,01.
f. Jam Kerja
Jam kerja waktu kerja bagi seseorang menentukan efisiensi dan
produktifitasnya. Lamanya seseoarang bekerja sehari secara baik pada
umumnya 6-8 jam. Sisanya 16-18 jam dipergunakan untuk kehidupan
dalam keluarga dan masyarakat, istirahat, tidur dan lain-lain.
Memperpanjang waktu kerja lebih dari kemampuan tersebut biasanya
tidak disertai efisiensi yang tinggi, bahkan biasanya terlihat penurunan
26
produktifitas serta kecenderuangan untuk timbulnya kelelahan, penyakit
dan kecelakaan kerja (Suma’mur, 1996). Menutut Suma’mur (1981)
bekerja merupakan proses anabolisme, yaitu mengurangi atau
menggunakan bagian-bagian tubuh yang telah dibangun sebelumnya.
Dalam keadaan demikian, sistem syaraf utama yang berfungsi adalah
komponen simpatis. Maka pada kondisi tersebut, aktifitas tidak dapat
dilakukan secara terus menerus, melainkan harus diselingi dengan
istirahat untuk memberikan kesempatan untuk membangun kembali
tenaga yang telah digunakan. Di Indonesia telah ditetapkan lamanya
waktu kerja sehari maksimum 8 jam kerja dan sisanya untuk
istirahat/kehidupan dalam keluarg adan masyarakat. Memperpanjang
waktu kerja lebih dari itu hanya akan menurunkan efisiensi kerja,
meningkatkan kelelahan kerja, kecelakaan dan penyakit akibat kerja
(Tarwaka et al, 2004). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2008)
kelelahan banyak terjadi pada pekerja yang bekerja selama 10 jam perhari
yaitu sebnyak 13 orang (28,9%), dengan P-value 1,89 yang menyatakan
tidak ada hubungan antara jam kerja dengan kelelaha kerja. Sedangkan
pada penelitian lainnya kelelahan banyak dialami oleh pekerja yang
bekerja dibawah 7 jam perhari, dengan P-value 0,854 yang menyatakan
tidak ada hubungan antara jam kerja dengan kelelahan kerja
(Andiningsari, 2009).
27
g. Masa Kerja
Tekanan melalui fisik (beban kerja) pada suatu waktu tertentuk
mengakibatkan berkurangnya kinerja otot, gejala yang ditunjukkan juga
berupa pada makin rendahnya gerakan. Keadaaan ini tidak hanya
disebabkan oleh suatu sebab tunggal seperti terlalu kerasnya beban kerja,
namun juga oleh tekanan–tekanan yang terakumulasi setiap harinya pada
suatu masa yang panjang. Keadaan seperti ini yang berlarut–larut
mengakibatkan memburuknya kesehatan, yang disebut juga kelelahan
klinis atau kronis. Perasaan lelah pada keadaan ini kerap muncul ketika
bangun di pagi hari, justru sebelum saatnya bekerja, misalnya berupa
perasaan kebencian yang bersumber dari perasaan emosi (Budiono dkk,
2003). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Eraliesa (2008)
dalam Mauludi (2010) terdapat hubungan antara masa kerja dengan
tingkat kelelahan, dengan nilai pvaluenya 0,002.
h. Aktivitas Fisik
Menurut Almatsier (2004) mengatakan bahwa aktivitas fisik dapat
didefinisikan sebagai gerakan fisik yang dilakukan oleh otot tubuh dan
sistem penunjangnya. Menurut Depkes RI (2006) aktivitas fisik adalah
pergerakkan anggota tubuh yang menyebabkan pengeluaran tenaga secara
sederhana minimal 30 menit dalam sehari selama 5 hari dalam seminggu
yang sangat penting bagi pemeliharaan fisik, mental, dan kualitas hidup
28
sehat. Aktivitas fisik juga dapat terjadi dalam melakukan aktivitas seperti
pekerjaan rumah, berkebun, melakukan hobi, rekreasi dan olahraga
(Allender & Spradley, 2001 dalam Achmanagara, 2012). Aktivitas fisik
yang berlebihan merupakan salah satu faktor terjadinya kelelahan (Pearl
Medic, 2011) Berbeda dengan hasil penelitian penelitian Mamuaja (2011)
menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang nyata (p>0,05) antara
tingkat kelelahan dengan tingkat aktivitas fisik hari kerja dan libur.
Aktivitas fisik yang benar dapat dilakukan secara bertahap hingga
mencapai 30 menit. Jika belum terbiasa dapat dimulai dengan beberapa
menit setiap hari dan ditingkatkan secara bertahap. Aktivitas fisik yang
dilakukan secara teratur mampu membakar kalori sehingga bermanfaat
untuk mengatur berat badan dan menguatkan sistem jantung dan
pembuluh darah.
Total volume aktivitas fisik dapat ditentukan kuantitasnya dengan
satuan MET-hours perhari atau perminggu. Yaitu, intensitas semua
aktivitas yang berbeda selama periode pengkajian dinyatakan dalam
ekuivalen MET yang dikalikan dengan waktu yang digunakanbagi semua
aktivitas. Cara ini sering digunakan untuk menyatakan total volume
aktivitas fisik ketika menggunakan metode kuesioner (Gibney, 2009dalam
Parubak, 2011).
International Physical Activity Questionnare (IPAQ) dikembangkan
pertama kali di Geneva pada tahun 1998 kemudianterus diujikan validitas
29
dan realibilitasnya mencakup 12 negara pada6 benua hingga tahun 2002.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa metode pengukuran ini dapat
digunakan untuk monitoring dan sistem surveilans secara daerah, nasional
maupun internasional serta dapat digunakan untuk proyek penelitian dan
perencanaan dan evaluasi program kesehatan masyarakat.
IPAQ mengukur berbagai aktivitas yang mencakup:
1. aktivitas di waktu luang
2. aktivitas pekerjaan rumah tangga dan berkebun
3. aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan
4. Aktivitas yang berhubungan dengan transportasi.
IPAQ terdiri atas IPAQ short forms dan IPAQ long form. IPAQ
short forms adalah instrumen yang terutama didesain untuk mengukur
aktivitas fisik pada orang dewasa untuk usia di atas 15tahun. IPAQ short
forms berisi tentang 3 aktivitas spesifik utama yang terdapat dalam 4
domain di atas. Aktvitas fisik spesifik tersebut adalah berjalan, aktivitas
dengan intensitas sedang, dan aktivitas dengan intensitas keras. Aktvitas
fisik yang diukur dalam kuesioner ini adalah yang dilakukan minimal 10
menit dalam 1 kali kegiatan. IPAQ long forms mencakup 4 domain yang
diukur yaitu aktivitas di waktu luang, aktivitas pekerjaan rumah tangga
dan berkebun, aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan, aktivitas
yang berhubungan dengan transportasi.
30
Level MET setiap intensitas adalah berjalan sebanyak 3.3 METs,
aktivitas sedang sebanyak 4.0 METs, dan aktivitas keras sebanyak 8.0
METs. Total aktivitas fisik atau total MET/menit-minggu dihitung
dengan:
Berjalan (MET x menit x hari) + Sedang (MET x menit x hari) +
Keras (MET x menit x hari).
Contoh perhitungan total aktivitas fisik misalnya, seseorang
melakukan aktvitas fisik sebanyak 30 menit selama 5 hari:
Level METs METs x Durasi x Frekuensi
Berjalan 3.3 x 30 x 5 = 495 MET-menit/minggu
Sedang 4.0 x 30 x 5 = 600 MET-menit/minggu
Keras 8.0 x 30 x 5 = 1200 MET-menit/minggu
TOTAL = 2295 MET-menit/minggu
Kemudian total aktivitas fisik tersebut disesuaikan dengan kategori
di bawah ini (IPAQ, 2005) :
1. Ringan
Merupakan level terendah dalam aktivitas fisik. Seseorang yang
termasuk ke dalam kategori ini adalah apabila tidak melakukan aktivitas
fisik apapun atau tidak memenuhi kriteria aktivitas fisik sedang dan berat.
2. Sedang
Dikatakan termasuk dalam aktivitas fisik sedang jika memenuhi
kriteria berikut:
31
a. Melakukan aktivitas fisik dengan intensitas kuat minimal 20 menit
selama 3 hari atau lebih,
b. Atau melakukan aktivitas fisik dengan intenistas sedang selama
minimal 5 hari dan atau berjalan minimal 30 menit setiap hari,
atau kombinasi berjalan, aktivitas fisik dengan intenistas sedang
atau keras selama 5 hari atau lebih yang menghasilkan total
aktivitas fisik dengan minimal 600 MET-menit/minggu.
3. Berat
Dikatakan termasuk dalam aktivitas fisik berat jika memenuhi kriteria
berikut:
a. Melakukan aktivitas fisik dengan intensitas keras selama 3 hari
atau lebih yang menghasilkan total aktivitas fisik minimal
sebanyak 1500 MET-menit/minggu,
b. atau jika melakukan kombinasi berjalan, aktivitas fisik dengan
intenistas keras atau kuat selama 7 hari atau lebih yang
menghasilkan total aktivitas fisik minimal sebanyak 3000
METmenit/minggu.
i. Jenis Kelamin
Laki laki dan wanita berbeda dalam hal kemampuan fisiknya,
kekuatan kerja ototnya. Depnaker (1993) mengatakan bahwa menurut
pengalaman ternyata siklus biologi pada wanita tidak mempengaruhi
kemampuan fisik, melainkan lebih banyak bersifat sosial dan kultural.
32
Pria dan wanita berbeda dalam kemampuan fisiknya, kekuatan kerja
ototnya. Perbedaan tersebut dapat dilihat melalui ukuran tubuh dan
kekuatan otot dari wanita relatif kurang jika dibandingkan pria. Kemudian
pada saat wanita sedang haid yang tidak normal (dysmenorrhoea), maka
akan dirasakan sakit sehingga akan lebih cepat lelah (Suma’mur, 1996).
j. Psikologis
Pekerjaan apapun akan menimbulkan reaksi psikologis bagi yang
melakukan pekerjaan itu. Reaksi tersebut dapat bersifat positif misalnya
senang, bergairah, dan merasa sejahtera atau reaksi yang bersifat negative
misalnya bosan, acuh, tidak serius, stress dan sebagainya (Notoatmodjo,
1997). Faktor psikologis memainkan peranan besar dalam menimbulkan
kelelahan (Suma’mur, 1986). Tenaga kerja yang mempunyai masalah
psikologis amatlah mudah mengidap suatu bentuk kelelahan kronis
(Budiono dkk., 2000). Salah satu penyebab dari reaksi psikologis adalah
pekerjaan yang monoton yaitu suatu kerja yang berhubungan dengan hal
yang sama dalam periode atau waktu yang tertentu, dan dalam jangka
waktu yang lama dan biasanya dilakukan oleh suatu produksi yang besar
(Budiono dkk, 2000). Rasa bosan merupakan manifestasi dari reaksi
suasana monoton (Nurminanto, 2003). Dalam hal ini kebosanan
merupakan ungkapan perasaan tidak enak secara umum, yakni perasaan
resah, kurang menyenangkan dan lelah (Anies, 2002). Rasa bosan dapat
dirasakan oleh siapa saja. Kebosanan biasanya banyak dialami oleh
33
pekerja dalam bidang industry misalnya saja operator mesin tenun, mesin
cetak dan sejenisnya yang sifatnya monoton dan berulang-ulang (Budiono
dkk, 2000 dalam Mauludi, 2010)
k. Keadaan Monoton
Kelelahan yang disebabkan oleh karena kerja statis berbeda
dengan kerja dinamis. Pada kerja otot statis, dengan pengerahan tenaga
50% dari kekuatan maksimum otot hanya dapat bekerja selama 1 menit.
Sedangkan pada pengerahan tenaga <20% kerja fisik dapat berlangsung
cukup lama. Tetapi pengerahan tenaga otot statis sebesar 15-20% akan
penyebabkan kelelahan dan nyeri jika pembebanan berlangsung
sepanjang hari (Tarwaka et al, 2004).
Menurut Nurmianto (2004) pembebanan otot secara statis jika
dipertahankan dalam waktu cukup lama akan mengakibatkan Repetition
Strain Injuries (RSI), yaitu nyeri otot, tulang, tendon, dan lain-lain yang
diakibatkan oleh jenis pekerjaan yang bersifat berulang (repetitive).
Menurut Marfu’ah (2007) pembebanan kerja fisik atau kerja otot
akibat gerakan otot, baik dinamis maupun statis dapat mempengaruhi
kelelahan tubuh. Kerja otot statis terjadi menetap untuk periode waktu
tertentu yang menyebabkan pembuluh darah tekanan dan perdaran darah
berkurang. Tidak adanya variasi kerja akan menimbulkan kejenuhan
kerja. Kejenuhan ini dapat terjadi karena pekerja melakukan pekerjaan
yang selalu sama setiap harinya, keadaan seperti ini cukup berpotensi
34
untuk menyebabkan terjadinya kelelahan kerja (Sisinta, 2005).Silaban
(1998) dalam Virgy (2011) mengemukakan bahwa kebosanan (kelelahan
mental) merupakan komponen penting dalam psikologis lingkungan kerja
yang disebabkan menghadapi pekerjaan yang berulang-ulang. Monoton
dan aktifitas yang tidak menyenangkan. Keadaan ini biasanya meningkat
pada pertengahan jam kerja dan menurun diakhir jam kerja.
l. Lingkungan Kerja
Di tempat kerja terdapat beberapa faktor yang mempengaruh
lingkungan keja seperti faktor fisik, faktor kimia, faktor biologis dan
faktor psikologis. Semua faktor tersebut dapat menimbulkan gangguan
terhadap suasana kerja dan berpengaruh terhadap kesehatan dan
keselamatan tenaga kerja (Tarwaka et al, 2004). Menurut Fitrani
(2000)dalam Umyati (2010) bahwa faktor lingkungan seperti suhu,
kebisingan, pencahayaan, dan vibrasi akan berpengaruh terhadap
kenyamanan fisik, sikap mental, dan kelelahan kerja.
Faktor-faktor lingkungan diantaranya, adalah:
1) Kebisingan
Menurut Suma’mur (1996) bunyi didengar sebagai rangasangan
pada telinga oleh getaran-getaran melalui media elastis, dan manakala
bunyi-bunyi tersebut tidak dikehendaki, maka dinyatakan sebagai
kebisingan. bunyi dinilai sebagi bising sangat relatif sekali, suatu
contoh misalnya music diskotik, bagi orang yang biasa mengunjungi
35
tempat itu tidak merasa suatu kebisingan, tetapi bagi orang-orang yang
tidak pernah berkunjung didiskotik akan merasa suatu kebisingan yang
menganggu (Gabriel, 1997dalam Mauludi, 2010).
Terdapat dua hal yang menentukan kualitas suatu bunyi, yaitu
frekuensi dan intensitasnya. Frekuensi dinyatakan dalam jumlah
getaran perdetik atau disebut hertz (Hz) dan intensitas atau arus enerti
persatuan luas biasanya dinyatakan dalam decibel (dB). Menurut
Sedarmayanti (2009) kebisingan merupakan bunyi yang tidak
dikehendaki oleh telinga karena dalam jangka panjang dapat
menganggu ketenangan bekerja, merusak pendengaran, dan
menimbulkan kesalahan komunikasi, bahkan kebisingan yang serius
dapat menyebabkan kematian. Menurut Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat
Kebisingan, tingkat kebisingan yang diperbolehkan untuk kawasan
perumahan dan pemukiman yaitu tidak lebih dari 55 dB. Menurut
Rusdjijati dan Widodo (2008), jika nilai kebisingan sudah melebihi
Nilai Ambang Batas yang ditetapkan, maka dapat mengakibatkan
ketidaknyamanan bagi manusia yang menerima kebisingan tersebut.
Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kebisingan di suatu
tempat. Menurut Mashuri (2007) dalam Anggrainiet. al (2012) ,
faktor-faktor tersebut terdiri dari jarak, serapan udara, angin, dan
permukaan bumi.
36
2) Penerangan
Penerangan ditempat kerja adalah salah satu sumber cahaya
yang menerangi benda-benda ditempat kerja. Banyak obyek kerja
beserta benda atau alat dan kondisi disekitar yang perlu dilihat oleh
tenaga kerja. Hal ini penting untuk menghindari kecelakaan yang
mungkin terjadi. Selain itu penerangan yang memadai memberikan
kesan pemandangan yang lebih baik dan keadaan lingkungan yang
menyegarkan (Suma’mur, 1996). Penerangan ditempat kerja
merupakan salah satu faktor yang perlu diupayakan
penyempurnaannya. Penerangan yang baik mendukung kesehatan
kerja dan memungkinkan tenaga kerja bekerja dengan lebih aman dan
nyaman, yang antara lain disebabkan karena mereka dapat melihat
objek yang dikerjakan dengan jelas, cepat dan tanpa upaya tambahan,
serta membantu menciptakan lingkungan kerja yang nikmat dan
menyenangkan.
Penerangan yang baik adalah adalah penerangan yang
memungkinkan tenaga kerja melihat pekerjaan dengan teliti, cepat dan
tanpa upaya yang tidak perlu serta membantu menciptakan lingkungan
kerja yang nikmat dan menyenangkan. Penerangan tempat kerja yang
tidak adekuat juga bisa menyebabkan kelelahan mata, akan tetapi
37
penerangan yang terlalu kuat dapat menyebabkan kesialuan. (Rasjid,
dkk 1989 dalam Virgy 2011)
Akibat-akibat penerangan yang buruk (Budiono dkk, 2003)
a) Kelelahan mata dengan berkurangnya daya efisiensi kerja
b) Kelelahan mental
c) Keluhan-keluhan pegal didaerah mata, dan sakit kepala sekitar
mata.
d) Kerusakan alat penglihatan.
e) Meningkatnya kecelakaan.
Standar intensitas penerangan perumahan dan lingkungan
pemukiman menurut Keputusan Menteri Kesehatan
(Kepmenkes) No.829/Menkes/SK/VII/1999 tentang persyaratan
kesehatan perumahan adalah minimal 60 lux dan tidak
menyilaukan mata.
3) Getaran
Getaran adalah beresonansinya tubuh manusia akibat adanya
sumber getaran yang dapat menimbulkan gangguan berupa gangguan
kesehatan (Depnaker, 1993). Menurut Budiono dkk (2003) getaran
adalah gerakan yang teratur dari benda atau media dengan arah bolak-
balik dari kedudukan kesetimbangannya. Getaran terjadi saat mesin
atau alat dijalankan dengan motor, sehingga pengaruhnya bersifat
mekanis.
38
Pengaruh getaran pada tenaga kerja dapat dibedakan:
a) Gangguan kenikmatan dalam bekerja
b) Mempercepat terjadinya kelelahan
c) Gangguan kesehatan
4) Suhu
Suhu nikmat bekerja sekitar 24-26°C bagi orang-orang
Indonesia. Suhu dingin mengurangi efisiensi dengan keluhan kaku atau
kurangnya koordinasi otot. Suhu panas terutama berakibat menurunnya
prestasi kerja pikir. Penurunan sangat hebat sesudah 32°C. suhu panas
mengurangi kelincahan, memperpanjang waktu reaksi dan waktu
pengambilan keputusan, menganggu kecermatan kerja otak,
mengganggu koordinasi syaraf perasa dan motoris (Suma’mur, 1996).
Menurut Suma’mur (1992) pada suhu udara yang panas dan
lembab, makin tinggi kecepatan aliran udara malah akan makin
membebani tenaga kerja. Pada tempat kerja dengan suhu udara yang
panas maka akan menyebabkan proses pemerasan kringat. Beberapa
hal buruk berkaitan dengan kondisi demikian dapat dialami oleh
tenaga kerja, salah satunya kelelahan kerja. Pekerja yang mengalami
kondisi demikian, sulit untuk mampu bereproduksi tinggi. Akibat
kelelahan kerja tersebut, para pekerja menjadi kurang bergairah kerja,
daya tanggap dan rasa tanggung jawab menjadi rendah, sehingga
seringkali kurang memperhatikan kualitas produk kerjanya.
39
Standar suhu perumahan dan lingkungan pemukiman
menurut Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes)
No.829/Menkes/SK/VII/1999 tentang persyaratan kesehatan
perumahan yaitu 18-30°C.
2.1.5 Proses Terjadinya Kelelahan Kerja
Kelelahan terjadi karena terkumpulnya produk-produk sisa dalam
otot dan peredaran darah, dimana produk-produk sisa ini bersifat
membatasi kelangsungan aktivitas otot. Ataupun mungkin bisa dikatakan
bahwa produk sisa ini mempengaruhi serat-serat syaraf dan sistem syaraf
pusat sehingga menyebabkan orang menjadi lambat bekerja jika sudah
lelah.
Makanan yang mengandung glikogen, mengalir dalam ubuh melalui
peredaran darah. Setiap kontraksi dari otot akan selalu diikuti oleh reaksi
kimia (oksigen glukosa) yang merubah glikogen menjadi tenaga, panas dan
asam laktat (produk sisa). Dalam tubuh dikenal fase pemulihan, yaitu suatu
proses untuk merubah asam laktat menjadi glikogen kembali dengan
adanya oksigen dari pernafasan, sehingga memungkinka otot-otot bisa
bergerak secara montinu. Ini berarti keseimbangan kerja bisa dicapai
dengan baik apabila kerja fisiknya tidak terlalu berat. Pada dasarnya
kelelahan ini timbul karena terakumulasinya produk-produk sisa-sisa dalam
otot dan peredaran darah yang disebabkan tidak seimbangnya antara kerja
dan proses pemulihan.
40
Secara lebih jelas proses terjarjadinya kelelahan fisik adalah sebagai
berikut :
a. Oksidasi glukosa dalam otot menimbulkan CO2, saerolatic, phospat, dan
sebagainya, dimana zat-zat tersebut terikat dalam darah yang kemudian
dikeluarkan aktu bernafas. Kelelahan terjadi apabila pembentukan zat-zat
tersebut tidak seimbang dengan proses pengeluarannya sehingga timbul
penimbunan dalam jaringan otot yang menganggu kegiatan otot
selanjutnya.
b. Karbohidrat yang didapat dari makanan diubah menjadi glukosa dan
disimpan dihati dalam bentuk glikogen. Setiap 1 cm3 darah normal akan
membawa 1 mm glukosa, berarti setiap sirkulasi darah hanya membawa 0,1
% dari sejumlah glikogen yang ada dalam hati. Karena bekerja, persendia
glikogen dalam hati akan menipis dankelelahan akan timbul apabila
konsentrasi glikogen dalam hai tingal 0,7%.
c. Dalam keadaan normal, jumlah udara yang masuk melalui pernafasab kira-
kira 4 liter/menit, sedangkan dalam keadaan kerja keras dibutuhkan udara
sekitar 15 liter/menit. Ini berarti pada suatu tingkat kerja tertentu akan
dijumpai suatu keadaan diman jumlah oksigen yang masuk melalui
pernafasan lebih kecil dari tingkat kebutuhan. Jika ini terjadi maka
kelelahan akan timbul, karena reaksi oksidasi dalam tubuh yaitu untuk
mengurangi asam laktat menjadi H2O (air) dan CO2 (karbondioksida) agar
dikeluarkan dalam tubuh, menjadi tidk seimbang dengan pembentukan
41
asam laktat itu sendiri (asam laktat terakumulasi dalam oot atau dalam
peredaran darah) (Satalaksana, 1979).
Untuk kelelahan psikologis, para ahli meyakini bahwa keadaan dan
perasaan dan kelelahan yang timbul karena adanya rekasi fungsional dari
pusat kesadaran (Cortex cerebri) yang atas pengaruh dua sistem
antagonistic yaitu sistem penghambat (inhibisi) dan sistem penggerak
(aktivasi). Sistem penghambat ini terdapat dalam thalamus, dan bersifat
menurunkan kemampuan manusia untuk bereaksi. Sedangkan sistem
penggerak terdapat dalam formation retikulasi yang bersifat dapat
merangsang pusat-pusat vegatif untuk konversi ergitropis dari peralatan-
peralatan tubuh kearah bereaksi. Dengan demikian, keadaan seseorang
pada suatu saat sangat tergantung pada hasil kerja kedu sistem tersebut
(Satalaksana, 1979)
Apabila sistem penggerak lebih kuat dari sistem penghambat, maka
keadaan orang tersebut ada dalam keadaan segar untuk bekerja.
Sebaliknya, apabila sistem penghambat lebih kuat dati sistem penggerak
maka orang akan mengalami kelelahan. Itulah sebabnya, seseorang yang
sedang lelah dapat melakukan akifitas secara tiba-tiba apabila mengalami
sesuatu peristiwa yang tidak terduga (ketegangan emosi). Demikian juga
kerja yang monoton bisa menimbulkan kelelahan walaupun beban
kerjanya tidak seberapa. Hal ini disebabkan karena sistem penghambat
lebih kuat dari pada sistem penggerak. (Satalaksana, 1979)
42
2.1.6 Akibat Kelelahan Kerja
Perubahan fisiologis akibat kelelahan merupakan kerja mekanisme
prinsip tubuh mencakup sistem sirkulasi, sistem pencemaan, sistem otot,
sistem saraf dan sistem pemafasan. Kerja fisik yang terus menerus
mempengaruhi mekanisme tersebut baik sebagian maupun secara
keseluruhan (Setyawati, 1994). Gejala kelelahan kerja menurut Gilmer
(1966) dan Cameron (1973) yaitu menurun kesiagaan dan perhatian,
penurunan dan hambatan persepsi, cara berpikir atau perbuatan anti sosial,
tidak cocok dengan lingkungan, (depresi, kurang tenaga, kehilangan
inisiatif), dan gejala umum (sakit kepala, vertigo, gangguan fungsi paru dan
jantung, kehilangan nafsu makan, gangguan pencemaan, kecemasan,
pembahan tingkah laku, kegelisahan, dan kesukaran tidur). Kelelahan kerja
dapat menyebabkan prestasi kerja yang menurun, fungsi fisiologis motorik
dan neural yang menurun, badan terasa tidak enak, Semangat kerja yang
menurun (Bartley dan Chute, 1982).
Beberapa penelitian mendapatkan hasil, bahwasanya kelelahan
kerja berhubungan dengan faktor fisik, faktor pekerjaan dan faktor
individu. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Atik Muftia pada bagian
produksi diperoleh ada hubungan antara penerangan dengan kelelahan
dengan nilai pvaluenya 0,032. Hasil penelitian yang dilakukan Paulina
(2008) pada proses produksi menunjukkan adanya hubungan tekanan panas
dengan kelelahan kerja dengan nilai pvaluenya 0,001, ada hubungan
43
antara umur dengan kelelahan kerja dengan nilai valuenya 0,0001 dan
ada hubungan antara masa kerja dengan kelelahan kerja dengan nilai
pvaluenya 0,0001.
2.1.7 Penanggulangan Kelelahan Kerja
Kelelahan disebabkan oleh banyak faktor. Yang terpenting adalah
bagaimana menangani setiap kelelahan yang muncul agar tidak menjadi
kronis. Agar dapat menangani kelelahan dengan tepat, maka harus
diketahui apa penyebab dari kelelahan tersebut (Tarwaka dkk, 2004).
Menurut Budiono (2000) dalam Maulidi (2010) Kelelahan dapat dikurangi
dengan berbagai cara:
a. Pengaturan jam kerja.
b. Pemberian kesempatan istirahat.
c. Adanya masa–masa libur dan rekreasi.
d. Penerapan ilmu ergonomi dalam bekerja.
e. Penggunaan musik ditempat kerja.
f. Memperkenalkan perubahan rancangan produk.
g. Merubah metoda kerja menjadi lebih efisien dan efektif.
h. Menciptakan suasana lingkungan kerja yang sehat, aman dan nyaman.
2.1.8 Pengukuran Kelelahan
Sampai saat ini belum ada metode pengukuran kelelahan yang baku
karena kelelahan merupakan suatu perasaan subjektif yang sulit diukur dan
diperlukan pendekatan secara multidisiplin (Grandjean, 1993) yang dikutip
44
oleh Tarwakadkk (2004). Namun demikian diantara sejumlah metode
pengukuran terhadap kelelahan yang ada, umumnya terbagi kedalam 5
kelompok yang berbeda, yaitu:
a. Kualitas dan Kuantitas Kerja yang Dilakukan
Pada metode ini, kualitas output digambarkan sebagai jumlah proses
kerja (waktu yang digunakan setiap item) atau proses operasi yang dilakukan
setiap unit waktu. Namun demikian banyak faktor yang harus
dipertimbangkan seperti; target produksi; faktor sosial; dan perilaku
psikologis dalam kerja. Sedangkan kualitas output (kerusakan produk,
penolakan produk) atau frekuensi kecelakaan dapat menggambarkan
terjadinya kelelahan, tetapi faktor tersebut bukanlah merupakan causal faktor
(Tarwaka dkk, 2004).
b. Pengujian Psikomotorik
Pada metode ini melibatkan fungsi persepsi, interpretasi dan reaksi
motor. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan pengukuran
waktu reaksi. Waktu reaksi adalah jangka waktu dari pemberian suatu
rangsang sampai kepada suatu saat kesadaran atau dilaksanakan kegiatan.
Dalam uji waktu reaksi dapat digunakan nyala lampu, denting suara,
sentuhan kulit atau goyangan badan. Terjadinya pemanjangan waktu reaksi
merupakan petunjuk adanya perlambatan pada proses faal syaraf dan otot.
Sanders dan Cormick (1987) yang dikutip oleh Tarwaka dkk (2004)
mengatakan bahwa waktu reaksi adalah waktu untuk membuat suatu respon
45
yang spesifik saat suatu stimulasi terjadi. Waktu reaksi terpendek biasanya
berkisar antara 150 s/d 200 milidetik. Waktu reaksi tergantung dari stimuli
yang dibuat; intensitas dan lamanya perangsangan; umur subjek; dan
perbedaan-perbedaan individu lainnya. Setyawati (1996) yang dikutip oleh
Tarwaka dkk (2004) melaporkan bahwa dalam uji waktu reaksi, ternyata
stimuli terhadap cahaya lebih signifikan daripada stimuli suara. Hal tersebut
disebabkan karena stimuli suara lebih cepat diterima oleh reseptor daripada
stimuli cahaya. Alat ukur waktu reaksi telah dikembangkan di Indonesia
biasanya menggunakan nyala lampu dan denting suara sebagai stimuli.
c. Mengukur Frekuensi Subjektif Kelipan Mata (Flicker Fusion Eyes)
Dalam kondisi yang lelah, kemampuan tenaga kerja untuk melihat
kelipan akan berkurang. Semakin lelah akan semakin panjang waktu yang
diperlukan untuk jarak antara dua kelipan. Uji kelipan, disamping untuk
mengukur kelelahan juga menunjukkan keadaan kewaspadaan tenaga kerja
(Tarwaka at al, 2004).
d. Perasaan Kelelahan Secara Subjektif (Subjektive Feelings of Fatigue)
Subjective Self Rating Tes dari Industrial Fatigue Research
Committee (IFRC) Jepang, merupakan salah satu kuesioner yang dapat untuk
mengukur tingkat kelelahan subjektif. Kuesioner tersebut berisi 30 daftar
pertanyaan yaitu:
1) Perasan berat dikepala
2) Menjadi lelah seluruh badan
46
3) Kaki merasa berat
4) Menguap
5) Merasa kacau pikiranm
6) Menjadi mengantuk
7) Merasa beban pada mata
8) Kaku dan canggung dalam gerakan
9) Tidak seimbang dalam berdiri.
10) Mau berbaring
11) Merasa susah berpikir.
12) Lelah bicara
13) Menjadi gugup
14) Tidak dapat berkonsentrasi
15) Tidak dapat memenuhi perhatian terhadap sesuatu.
16) Cenderung untuk lupa
17) Kurang kepercayaan.
18) Cemas terhadap sesuatu
19) Tak dapat mengontrol sikap
20) Tidak dapat tekun dalam pekerjaan.
21) Sakit kepala
22) Kekakuan di bahu
23) Merasa nyeri dipunggung
24) Merasa pernafasan tertekan
47
25) Haus
26) Suara serak
27) Merasa pening
28) Spasme dari kelopak mata.
29) Tremor pada nggota badan
30) Merasa kurang sehat.
Pertanyaan-pertanyaan 1-10 menunjukkan pelemahan kegiatan, 11-20
menunjukkan pelemahan motivasi dan 21-30 gambaran kelelahan fisik
akibat keadaan umum (Sumamur, 1986).
Metode pengukuran kelelahan menggunakan skala yang dikeluarkan
oleh Industrial Fatigue Committee (IFRC) atau dapat disebut Subjective
Syimtoms Test (SST) dimana berisi sejumlah pertanyaan yang berhubugan
dengan gejala-gejala kelelahan. Skala IFRC ini terdapat 30 gejala kelelahan
yang disususn dalam bentuk daftar pertanyaan. Jawaban untuk kuesioner
IFRC tersebut terbagi menjadi 4 kategori yaitu sangat sering (SS) dengan
diberi nilai 4, sering (S) dengan diberi nilai 3, kadang-kadang (K) dengan
diberi nilai 2, dan tidak pernah (TP) dengan diberi nilai 1. Dalam
menentukan tingkat kelelahan, jawaban tiap pertanyaan dijumlahkan
kemudian disesuaikan dengan kategori tertentu. Kategori yang diberikan
antara lain:
Nilai 30 : tidak lelah
Nilai 31-60 : kelelahan ringan
48
Nilai 61-90 : kelelahan menengah
Nilai 91-120 : kelelahan berat (Ariani 2009 dalamMauludi 2010)
e. Pengujian Mental
Pada metode ini konsentrasi merupakan salah satu pendekatan yang
dapat digunakan untuk menguji ketelitian dan kecepatan menyelesaikan
pekerjaan. Baurdon Wiersma Test, merupakan salah satu alat yang dapat
digunakan untuk menguji kecepatan, ketelitian dan konsentrasi. Hasil test
akan menunjukkan bahwa semakin lelah seseorang maka tingkat kecepatan,
ketelitian dan konsentrasi akan semakin rendah atau sebaliknya. Namun
demikian Bourdon Wiersma tes lebih tepat untuk mengukur kelelahan akibat
aktivitas atau pekerjaan yang lebih bersifat mental.
Menurut Grandjean (1985) yang dikutip oleh Setiarto (2002),
proses penerimaan rangsangan terjadi karena setiap rangsangan yang
datang dari luar tubuh akan melewati sistem aktivitas, yang kemudian
secara aktif menyiagakan korteks bereaksi. Dalam hal ini sistem aktivasi
retrikulasi befungsi sebagai distributor dan amplifier sinyal-sinyal tersebut.
Pada keadaan lelah secara neurofisiologis, korteks cerebri mengalami
penurunan aktivasi, terjadi perubahan pengarahan sehingga tubuh tidak
secara cepat menjawab sinyal-sinyal dari luar. Salah satu alat guna
mengetahui tingkat kelelahan adalah dengan Reaction Timer Test, yaitu alat
untuk mengukur tingkat kelelahan berdasarkan kecepatan waktu reaksi
seseorang terhadap rangsang cahaya dan rangsang suara. Pada keadaan yang
49
sehat, tenaga kerja akan lebih cepat merespon rangsang yang diberi dan
seseorang yang telah mengalami kelelahan akan lebih lama merespon
rangsang yang diberi (Koesyanto dan Tunggul, 2005 dalam Mauludi, 2010).
Menurut Koesyanto dan Tunggul (2005) dalam Mauludi (2010),
tingkat kelelahan kerja dapat diklasifikasikan berdasarkan waktu reaksi yang
diukur dengan reactiontimer yaitu:
Normal(N) : Waktu reaksi 150.0-240.0 milidetik.
Kelelahan Kerja Ringan (KKR) : Waktu reaksi >240.0<410.0 milidetik .
Kelelahan Kerja Sedang (KKS) : Waktu reaksi 410.0<580.0 milidetik .
Kelelahan Kerja Berat (KKB) : Waktu reaksi >580.0 milidetik.
Dari uraian metode pengukuran tersebut memiliki kelebihan
maupun kekurangan yang disajikan dalam Tabel 2.4 dibawah ini:
Tabel 2.4
Kelebihan dan Kekurangan Metode Pengukuran Kelelahan Kerja
No. Metode Kelebihan Kekurangan
1 Kualitas dan
kuantitas kerja yang
dilakukan
Kuantitas output
digambarkan sebagai
jumlah proses kerja,
waktu yang digunakan
setiap item atau jumlah
operasi yang dilakuka
setiap unit waktu
- Banyak faktor yang harus
dipertimbangkan seperti
target produksi, faktor
sosial, dan perilaku
psikologis dalam kerja
- Terkadang kelelahan
membutuhkan
pertimbangan dalam
hubungannnya dengan
kualitas output (kerusakan
produk, penolakan
50
No. Metode Kelebihan Kekurangan
produk) atau frekuensi
kecelakaan dapat
menggambarkan terjadinya
kelelahan, tetapi faktor
tersebut bukanlah merupakan
causal faktor
2 Pengujian
psikomotorik
Dapat diamati secara
langsung seseorang
mengalami kelelahan
Pada pengukuran ini, waktu
reaksi tergantung dari stimuli
yang dibuat, intensitas dan
lamanya perangsangan, umur
subjek, dan perbedaan-
perbedaan individu lainnya,
serta muncul suatu kenyataan
bahwa pada uji ini seringkali
membuat permintaan yang
sulit pada subjek yang diteliti,
sehingga dapat
mengakibatkan peningkatan
ketertarikan, pada pandangan
sebelumnya, sangat
memungkinkan bila uji ini
akan menyebabkan beberapa
jenis kegiatan yang
berhubungan dengan
penggunaan otak, diamana
dapat memungkinkan untuk
menimbulkan kelelahan.
3 Mengukur
frekuensi subjektif
kelipan mata
(flicker fusion eyes
test)
Disamping untuk
mengukur kelelahan
juga menunjukkan
keadaan kewaspadaan
tenaga kerja
Bisa terjadi bias dalam
menentukan besar frekuensi
yang dihasilkan dalam
pengukuran.
4 Perasaan kelelahan
secara subjektif
Kelelahan dapat
dianalisis langsung dari
gejala-gejala yang
dirasakan oleh
seseorang
Pengukuran bersifat subjektif
5 Pengujian mental Pengukuran
berdasarkan pengujian
mental yaitu
didapatkan hasil test
Lebih tepat untuk mengukur
kelelahan secara objektif
akibat aktivitas atau
pekerjaan yang lebih bersifat
51
No. Metode Kelebihan Kekurangan
yang akan
menunjukkan bahwa
semakin lelah
seseorang maka tingkat
kecepatan, ketelitian
dan konsentrasi akan
semakin rendah atau
sebaliknya.
mental.
6 Reaction Timer Test Kelelahan dapat
dianalisis langsung dari
hasil kecepatan
merespon suatu
rangsangan yang
diberikan
Pengukuran bersifat objektif
Alat yang digunakan dalam mengukur kelelahan ibu menyusui
dalam penelitian ini adalah Subjective Self Rating Tes dari Industrial Fatigue
Research (IFRC) yang merupakan kuesioner yang dapat mengukur tingkat
kelelahan secara subjektif. Selain itu, Reaction Timer Test juga digunakan
untuk pengukuran kelelahan yang bersifat objektif. Kedua alat ukur ini
dipilih karena sesuai fungsinya dan tidak memerlukan waktu yang cukup
lama yang dapat mengganggu kegiatan ibu dalam melakukan aktifitasnya.
2.2 Metode Penilaian Tingkat Risiko Ergonomi
Ergonomi merupakan suatu ilmu dengan metode dan model untuk
menganalisis tugas, merancang kerja, memprediksi kinerja, mengumpulkan data
tentang kinerja manusia dan interaksi dengan alat-alat serta lingkungan pada
interaksi semua hal teresebut terjadi
52
Postur tubuh dapat didenefisikan sebagai orientasi reaktif dari bagian
tubuh terhadap ruang. Untuk melakukan orientasi tubu tersebut selama beberapa
rentang waktu dibutuhkan kerja otot untuk menyangga atau menggerakkan
tubuh. Postur yang diadopsi manusia saat melakukan beberapa pekerjaan adalah
hubungan antara dimensi tubuh pekerja dengan dimensi beberapa benda dalam
lingkungan kerjanya (Phesant, 1991).
Posisi dalam kerja sangat ditentukan oleh jenis pekerjaan yang
dilakukan, masing-masing posisi kerja mempunyai pengaruh yang berbeda-beda
terhadap tubuh. Menurut Soeripto (1989), perencanaan dan penyesuaian alat
yang tepat bagi tenaga kerja serta kelestarian lingkungan kerja, dan juga
memperbaiki kualitas produk dari suatu proses produksi.
Dari poin-poin yang dapat dianalisis dan dievaluasi melalui metode
pengukuran risiko ergonomi (Risk Assesment Ergonomic), berguna juga untuk
mengetahui tingkat risiko kelelahan di tempat kerja. (Stanton et al, 2004 dalam
Umyati, 2010):
2.2.1 QEC (Quick Expssure Checklist)
Geoffrey David (2005),Quick Expssure Checklist (QEC) adalah
metode untuk mengukur risiko terkait faktor risiko MusculoskeletalWork-
Related Musculoskeletal Risk Faktors (WMSDs). Pekerjaan gangguan
muskuloskeletal terkait (WMSDs) adalah masalah kesehatan umum di
seluruh industri dunia dan penyebab utama kecacatan. WMSDs adalah
kondisisaraf, tendon, otot, dan mendukung struktur dari sistem
53
muskuloskeletal yang bisa menyebabkan kelelahan, ketidaknyamanan,
nyeri, pembengkakan lokal, atau mati rasa dan kesemutan.WMSDs
biasanya berkembang dari kumulatif ciderayang lama berbulan-bulan
bahkan bertahun-tahun akibat hubungan ke tingkatyang berlebihan fisik
dan psikososial stres di tempat kerja.
QEC melakukah pengukuran pada beberapa titik bagian tubuh
yaitu punggung, bahu dan lengan, pergelangan tanga serta Ieher. Selain
bagian tubuh tersebut, metode QEC juga melakukan pengukuran dengan
mempertimbangkan pada beban kerja dan waktu kerja. Beberapa ahli
mengernbangkan ahli metode ini pada beberapa perusahaan untuk hal-hal
berikut (Stanton et al, 2004 dalam Umyati, 2010):
a. Mengukur perbedaan risiko WMSDs pada sebelum dan sesudah
pekerjaan
b. Mengidentifikasi faktor risko untuk pekerjaan terkait cedera bagian
belakang.
c. Mengevaluasi level risiko untuk bagian tubuh yang berbeda.
d. Mengembangkan tempat kerja menjadi sarana dalam mengurang risiko
WMSDs dan mengurangi biaya yang dikeluarkan akibat WMSDs.
e. Membandingkan tingkat papaan yang diterima oleh dua pekerja atau
Iebih dengan pekerjaan yang sama, atau perbandingan risiko dengan
pekerjaan lainnya.
54
f. Meningkatkan kesadaran tingkat manajer, teknisi, desainer, kesehatan
dan pelaksana keselamatan terhadap faktor risiko ergonomi di tempat
keja.
Adapun kelebihan dalam menggunakan QEC adalah :
a. Mudah untuk diterapkan.
b. Membantu untuk melakukan perubahan ergonomi.
c. Selaras dengan metode pengukuran lainnya.
d. Melindungi bahaya fisik akibat WMSDs
e. Tidak perlu waktu lama untuk mempelajarinya.
f. Mempertimbangkan kombinasi bahaya yang ada di tempat kerja.
Adapun kekurangan dari metode ini adalah :
a. Metode ini hanya terfokus pada faktor fisik tempat kerja saja.
b. Skor/nilai paparan yang disarankan butuh validitas kembali.
c. Perlu pengembangan Iebih lanjut untuk memberikan pengukuran
yang tepat.
2.2.2 REBA (Rapid Body Assement)
REBA adalah metode yang dikembangkan oleh Sue Hignett dan
Lynn McAtamney yang secara efektif digunakan untuk menilai postur tubuh
pekerja. Selain itu metode REBA memperhitungkan beban yang ditangani
dalam watu sistem kerja, coupling dan aktivitas yang dilakukan. Metode ini
relatif mudah digunakan karena untuk mengetahui nilai suatu anggota
tubuh tidak diperlukan besar sudut yang spesifik, hanya berupa range
55
sudut. Pada akhirnya nilai akhir dari REBA memberikan indikasi level
risiko dari suatu pekerjaan dan tindakan yang harus dilakukan/diambil
(Stanton et al, 2004 dalam Umyati, 2010).
REBA dapat digunakan untuk penilaian risiko ergonomi ditempat
kerja melalui analisis postural
a. Seluruh tubuh yang digunakan.
b. Posturstatis, dinamis, cepat berubah, atau tidak stabil.
c. Animate atau beban kerja yang sedang ditangani baik sering atau
jarang.
d. Modifikasi tempat kerja, peralatan, pelatihan, atau mengambil risiko
perilaku pekerja adalah sedang dipantau pre/post perubahan.
Kelebihan menggunakan metode REBA adalah sebagai alat
analisis postur yang cukup sensitive untuk postur kerja yang yang sukar
diprediksi dalam bidang perawatan kesehatan dan industri lainnya. REBA
melakukan assessment berdasarkan postur-postur yang terjadi dari
beberapa bagian tubuh dan melihat beban atau tenaga yang dikeluarkan
serta aktifitasnya. Perubahan nilai-nilai disediakan untuk setiap bagian
tubuh, yang dimaksud untuk memodifikasi nilai dasar jika terjadi
perubahan atau pertambahan faktor risiko dari setiap pergerakan atau
postur yang dilakukan.
56
2.2.3 RULA (Rapid Upper Limb Assement)
RULA adalah sebuah penilaian yang mudah terhadap beban otot
rangka pada anggota tubuh bagian atas (upper limb) yaitu leher dan tangan.
Selain itu, RULA merupakan sebuah metode untuk menilai risiko
ergonomi dengan melihat postur, frekuensi, durasi, dan gaya gerakan suatu
aktivitas kerja yang berulang berkaitan dengan penggunaan anggota tubuh
bagian atas: leher, punggung, pergelangan tangan (Victorian, 1985).
Metode ini di kembangkan untuk menganalisis risiko yang akan dialami
oleh seorang pekerja dalam melakukan aktivitas kerja yang memanfaatkan
anggota tubuh bagian atas (upperlimb). Metode ini menggunakan diagram
postur tubuh dan tiga tabel penilaian untuk memberikan evaluasi terhadap
faktor risiko yang akan dialami oleh pekerja. Faktor-faktor risiko yang
diselidiki dalam metode ini adalah yang telah dideskripsikan oleh McPhee’
dalam Stanton (2004) dalam Umyati (2010) sebagai faktor beban eksternal
(external load faktors) yang meliputi :
a. Jumlah gerakan
b. Kerja otot statis
c. Gaya
d. Postur kerja yang ditentukan oleh perlengkapan dan perabotan
e. Waktu kerja tanpa istirahat
Kelebihan RULA adalah dapat menilai postur kerja dan hubungan
tingkatan risiko dalam waktu singkat dan hanya menggunakan pulpen,
57
kertas dan busur. Selain itu, RULA dapat menilai sebagian tugas atau
postur individu atau kelompok tertentu, membandingkan keberadaan serta
tujuan desain tempat kerja untuk dilakukan suatu perubahan ergonomi dan
menyediakan pengukuran objektif yang perubahannya dapat disarankan
dan diinvestigasi dengan tujuan utama yaitu mengimplementasikan solusi
praktek terbaik. Sedangkan kekurangan RULA dalah tidak didesain untuk
menyediakan postur secara rinci dan membutuhkan tools lain untuk
investigasi ergonomi yang lebih rinci.
Dalam melakukan pengukuran metode RULA mernbagi bagian
tubuh menjadi dua grup yaitu grup A dan B. Grup A meliputi bagian
lengan atas dan bawah, serta pergelangan tangan. Sementara grup B
meliputi Ieher, punggung, dan kaki. Hal ini untuk memastikan bahwa
seluruh postur tubuh terekam, sehingga segala kejanggalan atau batasan
postur oIeh kaki, punggung atau Ieher yang mungkin saja mempengaruhi
postur anggota tubuh bagian atas dapat tercakup dalam penilaian.
58
Tabel 2.5
Kelebihan dan Kekurangan Metode Pengukuran Risiko Ergonomi Postur Kerja
Metode Kelebihan Kekurangan
QEC (Quick
Expssure
Checklist)
a. Mudah untuk diterapkan.
b. Membantu untuk melakukan
perubahan ergonomi.
c. Selaras dengan metode
pengukuran lainnya.
d. Melindungi bahaya fisik
akibat WMSDs
e. Tidak perlu waktu lama
untuk mempelajarinya.
f. Mempertimbangkan
kombinasi bahaya yang ada
di tempat kerja.
a. Metode ini hanya
terfokus pada faktor
fisik tempat kerja saja.
b. Skor/nilai paparan
yang disarankan butuh
validitas kembali.
c. Perlu pengembangan
Iebih lanjut untuk
memberikan
pengukuran yang
tepat.
REBA (Rapid
Body Assement)
a. Sebagai alat analisis postur
yang cukup sensitive untuk
postur kerja yang sukar
diprediksi dalam bidang
perawatan kesehatan dan
industry lainnya.
b. REBA melakukan
assessment berdasarkan
postur-postur yang terjadi
dari beberapa bagian tubuh
dan melihat beban atau
tenaga yang dikeluarkan serta
aktifitasnya.
c. Perubahan nilai-nilai
disediakan untuk setiap
bagian tubuh, yang dimaksud
untuk memodifikasi nilai
dasar jika terjadi perubahan
atau pertambahan
faktorrisiko dari setiap
pergerakan atau postur yang
dilakukan.
a. Hanya menilai
aspek postur dari
pekerja.
b. Tidak
mempertimbangkan
kondisi yang
dialami oleh
pekerja terutama
yang berkaitan
dengan faktor
psikososial.
c. Tidak menilai
kondisi lingkungan
kerja terutama yang
berkaitan dengan
vibrasi,
temperature, dan
jarak pandang.
59
Metode Kelebihan Kekurangan
RULA (Rapid
Upper Limb
Assement)
a. menilai postur kerja dan
hubungan tingkatan
risiko dalam waktu
singkat.
b. sebuah penilaian yang
mudah terhadap beban
otot rangka pada anggota
tubuh bagian atas (upper
limb) yaitu leher dan
tangan
c. membutuhkan peralatan
yang mudah didapat
seperti pulpen, kertas,
kamera digital, busur dan
timbangan.
d. Metode RULA tidak
membutuhkan waktu
yang lama untuk
melengkapi dan
melakukan scoring
general yang nantinya
akan di amati.
e. memberikan sebuah
kemudahan dalam
menghitung rating dari
beban kerja otot dalam
bekerja dimana orang
mempuntai risiko pada
bagian leher dan beban
kerja pada anggota tubuh
bagian atas.
f. dapat digunakan untuk
menilai sebagian tugas
atau postur individu atau
kelompok tertentu.
g. membandingkan
keberadaan serta tujuan
desain tempat kerja untuk
dilakukan suatu
perubahan ergonomi dan
menyediakan pengukuran
a. tidak didesain untuk
menyediakan postur
secara rinci dan
membutuhkan tools lain
untuk investigasi
ergonomi yang lebih
rinci.
60
objektif yang
perubahannya dapat
disarankan dan
diinvestigasi dengan
tujuan utama yaitu
mengimplementasikan
solusi praktek terbaik.
Pada penelitian ini, peneliti memilih menggunakan metode RULA
dalam hal pengukuran terhadap risiko ergonomi, selain saat pengukuran
tidak mernbutuhkan alat tambahan khusus diluar alat seperti kamera dan
busur, hal ini juga di karenakan:
a. Metode RULA tidak membutuhkan waktu yang lama untuk
melengkapi dan melakukan scoring general yang nantinya akan di
amati.
b. Dalam pengukuran postur tubuh, metode RULA merupakan metode
yang menerapkan pengukuran pada penggunaan anggota tubuh bagian
atas tubuh saat beraktivitas yaitu penilaian terhadap beban otot rangka
pada anggota tubuh bagian atas (upper limb) yaitu leher dan tangan.
Hal tersebut, sangat sesuai dengan posisi yang digunakan ibu saat
menyusui.
c. Saat dilakukan survey pendahuluan penilaian terhadap kelelahan fisik
yang dirasakan oleh ibu, hampir seluruh ibu saat menyusui bayinya,
hampir seluruh bagian atas tubuh terjadi kelelahan fisik seperti merasa
nyeri dibagian punggung dan bahu terasa kaku dll.
61
2.2.3.1 Prosedur Penilaian Pengukuran RULA
Penilaian pengukuran RULA terjadi dalam tiga tahap. Tahap pertama
adalah pengembangan untuk perekaman atau pencatatan postur kerja, tahap ke
dua adalah pengembangan sistem penskoran (scoring) dan ketiga adalah
pengembangan skala level tindakan yang memberikan suatu panduan terhadap
level risiko dan kebutuhan akan tindakan untuk melakukan pengukuran yang
lebih terperinci. Penilaian menggunakan RULA merupakan metode yang telah
dilakukan oleh Me Atamney dan Eorlett (1993).Tahap-tahap menggunakan
metode RULA adalah sebagai berikut:
a. Penilaian Postur Tubuh Grup A
Postur tubuh group A terdiri dari lengan atas (upper arm), lengan bawah
(lower arm), pergelangan atas (wrist) dan putaran pergelangan tangan (wrist
wirst)
1. Lengan Atas (Upper Arm)
Penilaian terhadap lengan atas adalah penilaian yang dilakukan terhadap
sudut yang dibentuk lengan atas pada saat melkukan aktivitas kerja. Sudut
yang dibentuk lengan atas pada saat melakukan aktivitas kerja. Sudut
yang dibentuk oleh lengan atas diukur menurut posisi batang tubuh.
Adapun postur lengan atas dapat dilihat pada gambar 2.1
62
Gambar 2.1 Range Pergerakan Lengan Atas (A) Postur Alamiah, (B) Postur
Extensiondan Flexion Dan (E) Postur Lengan Flexion
Rentang untuk lengan bawah dikembangkan dari penelitian
Granjeibun Tiehauer. Skor tersebut adalah:
Tabel 2.6 Skor Bagian Lengan Atas (Upper Arm)
Pergerakan Skor Skor Perubahan
20˚ (kedepan maupun ke belakang
dari tubuh)
1 +1 jika bahu naik dan +1
jika lengan berputar
bengkok +20˚ (kebelakang atau 20˚-45˚) 2
20˚-90˚ 3
+90˚ 4
2. Lengan Bawah (Lower Arm)
Penilaian terhadap lengan bawah adalah penilaian yang dilakukan
terhadap sudut yang dibentuk lengan bawah pada saat melakukan
63
aktivitas kerja. Sudut yang dibentuk oleh lengan bawah diukur menurut
posisi batang tubuh. Adapun postur lengan bawah (lower Arm) dapat
dilihat pada gambar 2.2
Gambar 2.2 Range Pergerakan Lengan Bawah (A) Postur Flexion
(B)Postur Alamiah dan (E) Postur +100˚
Panduan untuk pergelangan tangan dikembangkan dari penelitian
Health and Safety Exeeutive , digunakan untuk menghasilkan skorpostur
sebagai berikut:
Tabel 2.7 Skor Bagian Lengan Bawah
Pergerakan Skor Skor perubahan
60°-100° 1 Jika lengan bawah bekerja melewati
garis tengah atau keluar dari sisi tubuh <60°atau 100° 2
3. Pergelangan Atas (Wrist)
Penilaian terhadap pergelangan tangan adalah penilaian yang dilakukan
terhadap sudut yang dibentuk oleh pergelangan tangan pada saat
melakukan aktivitas kerja. Sudut yang dibentuk oleh pergelangan tangan
64
diukur menurut posisi lengan bawah. Adapun postur pergelangan tangan
dapat dilihat pada gambar 2.3
Gambar 2.3 Range Pergerakan Tangan (A), (B) Postur Flexion 15˚+,
(E)Postur 0˚-15˚ Flexionmaupun Extension, (E) Postur Extension 15˚
Putaran pergerakan tangan (pronation dan supination ) yang
dikeluarkan oleh health and safety exeeutive pada postur netral berdasar
pada Tiehauer. Skor tersebut adalah:
Tabel 2.8 Skor Bagian Pergelangan Tangan
Pergerakan Skor Skor perubahan
Posisi Netral 1 +1 jika pergelangan tangan
putaran menjauhi sisi tengah 0˚-15˚ (ke atas maupun ke bawah) 2
>15˚(ke atas maupun ke bawah) 3
4. Putaran Pergelangan Tangan (Wrist Wirst)
Adapunpostur putaran pergelangan tangan dapat dilihat pada gambar 2.4
65
Gambar 2.4. Range Pergerakan Pergelangan Tangan dengan Postur Alamiah
Untuk putaran pergelangan tangan (wrist twist) postur netral diberi skor:
1= posisi tengah dari putaran
2= pada atau dekat putaran
Nilai dari postur lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan dan
putaran pergelangan tangan dimasukkan kedalam tabel postur tubuh grup A
untuk memperoleh skor seperti terlihat pada tabel.
66
Tabel 2.9 Worksheet RULA
2. Penambahan Skor Aktivitas
Setelah diperoleh hasil skor untuk postur tubu grup A pada tebel 2.9, maka
hasil skor tersebut ditambahkan dengan skor aktivitas. Penambahan skor
aktivitas tersebut berdasarkan kategori yang dapat dilihat pada tabel 2.9
Tabel 2.10 Skor Aktivitas
Aktivitas Skor Keterangan
Postur static +1 Satu atau lebih bagian tubuh statis/diam
pengulangan +1 Tindakan dilakukan berulang-ulang
lebih dari 4 kali permenit
67
3. Penambahan skor beban
Setelah diperoleh hasil penambahan dengan skor aktivitas untuk postur
tubuh grup B pada tabel 2.9, maka hasil skor tersebut ditambahkan dengan
skor beban. Penambahan skor beban tersebut berdasarkan kategori yang
dapat dilihat pada tabel 2.11
Tabel 2.11 Skor Beban
Beban Skor Keterangan
<2 kg 0 +1 jika postur statis
dilakukan berulang-
ulang
2kg-10 kg 1
>10 kg 3
b. Penilaian Postur Tubuh B
Postur tubuh grup B terdiri dari leher (neck), batang tubuh (trunk), dan kaki
(legs).
1. Leher (neck)
Penilaian terhadap leher adalah penilaian yang dilakukan terhadap posisi leher
pada saat melkukan aktivitas kerja apakah harus melkukan kegiatan ekstensi
atau fleksi dengan sudut tertentu. Adapun postur leher dapat dilihat pada
gambar 2.5.
68
Gambar 2.5 Postur Tubuh Bagian Leher
Skor penilaian untuk leher dapat dilihat pada tabel 2.12
Tabel 2.12Skor Bagian Leher
Pergerakan Skor Skor Perubahan
0°-10° 1 +1 jika leher berputar/bengkok
+1 batang tubuh bengkok 10°-20° 2
>20° 3
Ekstensi 4
2. Batang Tubuh (Trunk)
Penilaian terhadap batang tubuh adalah penilaian yang dilakukan terhadap
sudut yang dibentuktulang belakang tubuh saat melakukan aktivitas kerja
dengan kemiringan yang sudah diklasifikasikan. Adapun klasifikasi
kemiringan batang tubuh saat melkukan aktivitas kerja dapat dilihat pada
gambar 2.6
69
Gambar 2.6.Range Pergerakan Punggung (A) Postur 20° - 60°Flexion, (B)
Postur Alamiah, (E) Postur 0° - 20°Flexion Dam (D) Postur 60°atau Lebih Flexion
Skor penilaian bagian batang tubuh dapat dilihat pada tabel 2.13
Tabel 2.13 Skor Bagian Batang Tubuh
Pergerakan Skor Skor Perubahan
Posisi normal (90°) 1 +1 jika leher
berputar/bengkok
+1 jika batang tubuh
bungkuk
0°-20° 2
20°-60° 3
>60° 4
3. Kaki (legs).
Penilaian terhadap kaki adalah penilaian yang dilakukan terhadap posisi kaki
pada saat melakukan aktivitas kerja apakah bekerja dengan posisi normal
/seimbang atau bertumpu pada satu kaki lurus. Adapun posisi kaki dapat
dilihat pada gambar 2.7
70
Gambar 2.7.Range Pergerakan Kaki (A) Kaki Tertopang, Bobot Tersebar
Meratadan (B) Kaki Tidak Tertopang, Bobot Tidak Tersebar Merata
Tabel 2.14 Skor Penilaian untuk Kaki
Pergerakan Skor
Posisi normal/seimbang 1
Tidak seimbang 2
Nilai dari skor postur tubuh leher, batang tubuh, dan kaki dimasukkan ke
Tabel2.14
Tabel 2.15 Skor Grup B Trunk Postur Score
71
4. Penambahan Skor Aktifitas
Setelah diperolehhasil skor untuk postur tubuh grup B pada tabel 2.15, maka
hasil skor tersebut ditambahkan dengan skor aktivitas. Penambahan skor
aktivitas tersebut berdasarkan kategori yang dapat dilihat pada tabel 2.16
Tabel 2.16 Skor Aktivitas
Aktivitas Skor Keterangan
Postur statik +1 Satu atau lebih bagian tubuh statis/diam
Pengulangan +1 Tindakan dilakukan berulang-ulag lebih
dari 4 kali permenit
5. Penambahan Skor Beban
Setelah diperoleh hasil penambahan dengan skor aktivitas untuk postur
tubuh grup B pada Tabel 2.16, maka hasil skor tersebut ditambahkan dengan
skor beban. Penambahan skor beban tersebut berdasarkan kategori yang
dapat dilihat pada Tabel 2.18
Tabel 2.17 Skor Beban
Beban Skor Keterangan
<2 kg 0 +1 jika postur statis dan
dilakukan berulang-
ulang
2 kg-10 kg 1
>10 kg 3
72
Tabel 2.18 Grand Total Score
Hasil skor dari tabel 2.17 tersebut diklasifikasikan kedalam beberapa
kategori level risiko pada tabel 2.19
Tabel 2.19 Kategori Tindakan RULA
Kategori Tindakan Level Risiko Tindakan
1-2 minimum Aman
3-4 Kecil Diperlukan beberapa aktu ke depan
5-6 Sedang Tindakan dalam waktu dekat
7 Tinggi Tindakan sekarang juga
73
2.3 Menyusui
Menurut Soejono (1985), menyusui merupakan pekerjaan biologik yang
mulia bagi semua jenis mamalia dan sebagai satu kesatuan dari fungsi
reproduksi. Menyusui merupakan ketrampilan yang dipelajarai ibu dan bayi,
dimana keduanya membutuhkan waktu dan kesabaran untuk pemenuhan nutrisi
pada bayi selama enam bulan (Health, 2000). Menurut Farrer (1999) menyususi
merupakan pekerjaan yang menyenangkan dan tidak terlalu memberatkan begitu
pekerjaan ini berhasil dilaksanankan.
2.3.1. Keuntungan dari Menyusui
Keuntungan menyusui meningkat seiring dengan meningkatnya
lama pemberian ASI sampai dua tahun atau lebih (Roesli, 2008). Farrer
(1999) menjelaskan manfaat menyusui bagi bayi yaitu untuk keamanan
digesti bayi, ASI mengandung antibodi sehingga bayi yang mendapat
ASI umumnya jarang sakit dan jarang menderita alergi jika dibandingkan
dengan bayi yang mendapatkan susu formula, dan bayi yang disusui
sendiri akan memperoleh kesempatan didekap ibunya. Bagi ibu selain
memberikan manfaat fisik dengan membantu involusi uterus, mengurangi
insiden kanker payudara, menghemat waktu dan uang juga memberikan
kepuasan emosional dengan timbulnya persaan berhasil dalam
pemenuhan tugas sebagai ibu. Sejalan dengan pendapatnya Roesli (2008)
manfaat menyusui bagi bayi yaitu ASI mengandung nutrisi yang optimal,
baik kuantitas maupun kualitasny, ASI meningkatnkan kesehatan bayi,
74
ASI meningkatkan kecerdasan bayi, ASI meningkatkan jalinan kasih
saying ibu-anak (bonding). Keuntungan menyusui bagi ibu yaitu
mengurangi risiko kanker payudara (ca mamma), mengurangi risiko
kanker indung telur (ca ovarium) dan kanker rahim (ca endometrium),
mengurangi risiko keropos tulang (osteoporosis), mengurangi risiko
rheumatoid arthritis, metode KB paling aman, mengurangi risiko
diabetes maternal, mengurangi stress dan gelisah, berat badan lebih cepat
kembali normal.
2.3.2 Frekuensi dan Lama Menyususi
Disebutkan dalam buku An Easy Guide to Breastfeeding bahwa
menyusui dilakukan minimal 2 jam sekali, namun waktu menyusui ini
tidak boleh dijadwal secara ketat karena semakin sering bayi menyusu,
maka akan menstimulasi payudara ibu untuk memproduksi lebih banyak
ASI.
Menurut Fredregill (2010) menyusui dilakukan selama bayi mau,
rata-rata 15 sampai 30 menit pada beberapa minggu pertama.
Soetjiningsih (1997) menyatakan bahwa setelah produksi ASI cukup, bayi
dapat disusukan pada kedua buah payudara secara bergantian, tiap
payudara sekitar 10-15 menit (tidak boleh lebih dari 20 menit) dan
Fredregill (2010) menyatakan bahwa untuk mengosongkan payudara,
sangat jarang dibutuhkan waktu lebih dari 20 menit per payudara.
Semakin sering menyusui, selain kebutuhan ASI bayi terpenuhi, juga
75
untuk memberikan isyarat kepada tubuh ibu untuk memproduksi ASI
lebih banyak sebagai persiapan kebutuhan pertumbuhan bayi.
2.3.3 Posisi dan Perlekatan Menyusui
Riksani dalam keajaiban ASI menyebutkan bahwa masalah dalam
menyusui muncul sebab bayi tidak diposisikan pada payudara secara
tepat. Terdapat berbagai macam posisi menyusui, namun posisi yang baik
adalah kepala dan badan bayi berada pada garis lurus sehingga bayi dapat
menyusu dengan nyaman. Selain itu posisi ibu juga harus nyaman.
Ada berbagai macam posisi menyusui yang baik dan perlu diketahui
oleh para ibu. Hal ini penting karena berkaitan dengan kenyamanan yang
didapat baik oleh ibu maupun bayi. Posisi menyusui yang baik dapat
menjaga kesehatan puting susu, menghindarkan luka lecet pada puting
sehingga memungkinkan bayi menyusu (mendapatkan susu) secara
efisien.
Menurut Widodo (2011) posisi yang paling banyak digunakan ibu
saat menyusui terutama pada masa-masa awal menyusui adalah posisi
duduk yang berupa posisi cradle hold, cross cradle, dan football hold.
a. Cradle Hold
Posisi ini adalah yang paling banyak dipraktekkan ibu menyusui.
Posisi ini baik digunakan untuk wanita yang baru saja operasi caesar, bayi
yang berusia satu bulan atau lebih, dan menyusui saat sedang bepergian
76
karena tidak terlalu memerlukan penyangga (lengan ibu sebagai
penyangga).
Cara:
1) Ibu duduk pada kursi berlengan yang nyaman, punggung tegak (boleh
disangga dengan bantal agar dapat bersandar dengan nyaman). Jaga
agar posisi tidak membungkuk karena akan cepat lelah.
2) punggung hingga bokong bayi ditempatkan pada lengan bawah ibu.
lengan yang digunakan adalah lengan pada sisi yang sama dengan
payudara yang akan digunakan untuk menyusui (lengan kanan saat
akan menyusui dengan payudara kanan).
3) Kepala dan leher bayi ditempatkan pada lekuk siku.
4) Dekatkan kepala (bibir) bayi pada payudara dengan mengangkat
lengan (bukan membungkuk).
b. Cross Cradle
Posisi ini baik digunakan pada hari-hari pertama setelah
melahirkan, ibu yang baru belajar menyusui, dan bayi prematur. Pada saat
ibu berada pada posisi ini, ibu sebaiknya duduk tegak dengan bayi
didekatkan pada payudara dan bukan ibu yang membungkuk untuk
mendekatkan payudara ke bayi.
Cara:
77
1) Ibu duduk pada kursi berlengan yang nyaman, punggungtegak (boleh
disangga dengan bantal agar dapat bersandar dengan nyaman). Jaga
agar posisi tidak membungkuk karena akan cepat lelah.
2) Tanganibu pada sisi yang berseberangan dengan payudara yang
menyusui, memegang kepala dan leher bayi (tangankanan digunakan
bila akan menyusui dengan payudara kiri, dan sebaliknya).
3) Punggung dan bokong bayi disangga dengan lengan bawah ibu pada
tangan yang sama.
4) Tangan dapat digunakan untuk mengarahkan bayi ke payudara.
c. Football Hold
Dinamakan football karena Anda memegang bayi seperti
memegang bola football pada sisi tubuh (di bawah ketiak). Posisi ini baik
untuk ibu yang baru menjalani operasi caesar (yang sudah boleh duduk),
bayi kembar, dan untuk ibu yang memiliki ukuran payudara sangat besar.
Cara:
1) Punggung hingga bokong bayi ditempatkan pada lengan bawah ibu,
dengan daerah bokong pada lipat siku ibu. Lengan yang digunakan
adalah lengan pada sisi yang sama dengan payudara yang akan
digunakan untuk menyusui (lengan kanan saat akan menyusui dengan
payudara kanan).
2) Lengan ibu tidak ditempatkan di depan tubuh, namun di samping
(seperti mengapit tas).
78
3) Telapaktangan ibu menyangga kepala dan leher bayi, seluruh tubuh
bayi menghadap ke payudara (sisi tubuh) ibu.
4) Letakkan penyangga (bantal atau bantal menyusui) pada sisi tubuh
yang digunakan, di bawah lengan ibu dan tubuh bayi.
Tanda ibu belum menyusui bayi dengan benar
Berikut ini merupakan tanda-tanda ibu belum menyusui bayi dengan
benar
1. Kepala bayi tidak lurus dengan badannya
2. Bayi hanya menyusu pada putting, tidak meyusu pada areola dengan
putting susu masuk jauh kedalam mulutnya
3. Bayi menyusu dengan ringan, cepat dan gugup tidak menyusu
dengan sungguh-sungguh dan teratur
4. Pipinya berkerut kearah dalam atau ibu mendengar suara “cik-cik”
5. Ibu tidak mendengar bayinya menelan secara teratur setelah produksi
susunya meningkat.
Gambar 2.4
Posisi Cradle Hold
Gambar 2.5
Posisi Cross Cradle
Gambar 2.6
Posisi Football Hold
79
2.3.4 Langkah-langkah Menyusui yang Benar
Menurut Soetjiningsih (1997) langkah-langkah menyusui yang
benar adalah sebagai berikut:
1. Sebelum menyusui ASI dikeluarkan sedikit, kemudian dioleskan pada
puting dan disekitar kalang payudara. Cara ini mempunyai manfaat
sebagai disinfektan dan menjaga kelembaban putting susu.
2. Bayi diletakkan menghadap perut ibu/payudara.
- Ibu duduk atau berbaring dengan santai, bila duduk lebih baik
menggunakan kursi yang rendah (agar kaki ibu tidak
menggantung) dan punggung ibu bersandar pada sandaran kursi.
- Bayi dipegang pada belakan bahunya dengan satu lengan, kepala
bayi terletak pada lengkung siku ibu (kepala tidak boleh
menengadah, dan bokong bayi ditahan dengan telapak tangan).
- Satu tangan bayi diletakkan dibelakang badan ibu, dan yang satu
di depan.
- Perut bayi menempel pada badan ibu, kepala bayi menghadap
payudara (tidak hanya membelokkan kepala bayi).
- Telinga dan lengan bayi terletak pada satu garis lurus.
- Ibu menatap bayi dengan kasih sayang.
3. Payudara dipegang dengan ibu jari diatas dan jari yang lain menopang
dibawah, jangan menekan putting susu atau kalang payudara saja.
80
4. Bayi diberi rangsangan agar membuka mulut (rooting reflex) dengan
cara:
- Menyentuh pipi dengan puting susu atau,
- Menyentuh sisi mulut bayi.
5. Setelah bayi membuka mulut, dengan cepat kepala bayi didekatkan
kepayudara ibu dan putting serta kalang payudara dimasukkan
kemulut bayi:
- Usahakan sebagian besar kalang payudara dapat masuk kemulut
bayi, sehingga putting susu berada dibawah langit-langit dan lidah
bayi akan menekan ASI keluar dari tempat penampungan ASI
yang terletak dibawah kalang payudara. Posisi yang salah
yaituapabila bayi hanya menghisap pada putting susu saja, akan
mengakibatkan masuk ASI yang tidak adekuat dan puting susu
lecet.
- Setelah bayi mulai menghisap payudara tak perlu dipegang atau
disangga lagi.
81
2.4 Kerangka Teori
Berdasarkan teori yang dikatakan oleh Suma’mur (1996) Grandjean
(1988), Siswanto (1999), Oentoro(2004), Tarwaka (2004) dan Milligan (1996)
mengenai beberapa faktor utama yang signifikan yang menyebabkan terjadinya
kelelahan, meliputi: risiko ergonomi postur kerja, masa kerja, status gizi,
status pernikahan, psikolgis, kebiasaa merokok, jenis kelamin, usia, beban
kerja, aktivitas fisik,jam kerja, monotonnya pekerjaandan penyebab yang
berkaitan dengan tempat kerja (suhu ruang kerja, penerangan, kebisingan,).
Berdasarkan teori yang telah disebutkan bahwasanya ada beberapa faktor-faktor
yang menyebabkan terjadinya kelelahan. Untuk lebih mudahnya dapat dilihat
kerangka teori di bawah ini.
82
Karakteristik Individu:
Karakteristik Pekerjaan:
Sumber : Modifikasi dari teori Grandjean (1988), Suma’mur (1996) , Budiono dkk
(2003), Oentoro(2004), Tarwaka et al (2004) dan Milligan (1996) .
Gambar 2.1
Kerangka teori
1. Jenis Kelamin
2. Usia
3. Kebiasaan Merokok
4. Status Gizi
5. Psikologis
6. Status Pernikahan
7. Aktivitas fisik
8. Masa kerja Kelelahan Kerja
1. Risiko Ergonomi
postur kerja
2. Keadaan Monoton
3. Jam Kerja
4. Lingkungan Kerja
- Suhu
- Kebisingan
- Pencahayaan
- Getaran
83
BAB III
KERANGKA KONSEP, DEFINISI OPERASIONAL, DAN HIPOTESIS
3.1 Kerangka Konsep
Kerangka konsep ini mengacu pada kerangka teori yang ada, dimana pada
variabel terikat (dependen) dan variabel bebas (independen). Variabel bebas
(dependen) yaitu risiko ergonomi postur menyusui, usia, kebiasaan
merokok,status gizi, jam kerja (lama menyusui),aktivitas fisik dan lingkungan
pekerjaan (suhu, kebisingan dan pencahayaan). sedangkan kelelahan ditetapkan
sebagai variabel terikat (independen).
Berkaitan dengan jenis pekerjaan yaitu menyusui merupakan jenis
pekerjaan yang statis yaitu bekerja dengan punggung, dan leher pada 20 derajat,
bekerja dengan menahan beban menggunakan lengan bawah 60-100 derajat.
Pada faktor pekerjaan diukur dengan menggunakan metode RULA yaitu metode
pengukuran risiko ergonomi berdasarkan postur, frekuensi, durasi, dan gaya
gerakan suatu aktivitas kerja yang berulang berkaitan dengan penggunaan
anggota tubuh bagian atas: leher, punggung, pergelangan tangan (Victorian,
1985).
Berdasarkan kerangka teori pada tinjauan pustaka, tidak semua masuk
dalam kerangka konsep, hal ini disebabkan bahwa faktor-faktor yang masuk
dalam kerangka konsep merupakan faktor-faktor terpenting yang harus diketahui
84
dan diamati lebih dahulu sebagai penyebab terjadinya kelelahan pada responden.
Adapun variabel-variabel lain yang tidak diteliti yaitu:
a. Jenis kelamin
Jenis kelamin tidak diteliti karena ditempat penelitian homogen atau seluruh
responden berjenis kelamin perempuan
b. Status pernikahan
Satatus pernikahan tidak diteliti karena homogenya itu seluruh ibu berstatus
menikah
c. Masakerja
Masa kerja tidak diteliti karena homogeny yaitu ibu yang menyusui dibawah
enam bulan
d. Psikologis
Faktor psikologis merupakan faktor yang subyektif sehingga sulit didapatkan
hasil yang pasti atau signifikan
e. Getaran
Variabel Getaran tidak diteliti karena dilingkungan pekerjaan tidak ditemukan
sumber getaran
85
Berdasarkan kerangka teori maka kerangka konsep yang digunakan dalam
penelitian ini seperti pada bagan 3.1.
Gambar 3.1 Bagan Kerangka Konsep
1. Tingkat Risiko
Ergonomi Postur
Menyusui
2. Usia
3. Kebiasaan Merokok
4. Status Gizi
5. Jam Kerja (Lama
Menyusui)
6. Aktivitas Fisik
7. Faktor Lingkungan
- Suhu
- Kebisingan
- Pencahayaan
Kelelahan pada
Saat Menyusui
86
3.1 Definisi Operasional
Tabel 3.1
Definisi Operasional
No Variabel Definisi Alat Ukur Cara Ukur Hasil Ukur Skala
1. Kelelahan
pada Saat
Menyusui
Menurunnya kapasita dan ketahanan
menyusui yang ditandai oleh sensasi
lelah dan reaksi motoribu.
Reaction Timer Test
Pengukuran
lansung
0. Lelah (Waktu
reaksi >240.0
milidetik)
1. TidakLelah
(Waktu reaksi
≤240.0
milidetik.)
Ordinal
2 Risiko
Ergonomi
Postur
menyusui
Risikoposisi duduk saat menyusui
dengan melakukan penilaian dengan
melihat postur, gaya, gerakan suatu
aktifitas kerja,dan beban berdasarkan
metode RULA.
Observasi Form
penilaian
RULA,
Kamera
digital, dan
busur
derajat
Skor Ratio
3 Usia Jumlah tahun yang dihitung mulai dari
responden lahir hingga saat penelitian
berlangsung (Sisinta, 2005).
Kuesioner Wawancara Tahun Ratio
4 Lama
Menyusui
Total lama ibu menyusui dalam sehari.
Kuesioner Wawancara Jam Ratio
87
No Variabel Definisi Alat Ukur Cara Ukur Hasil Ukur Skala
5 Kebiasaan
Merokok
Kegiatan atau aktifitas menghisap
batang rokok/merokok yang dilakukan
oleh ibu dilihat dari hasil jumlah rata-
rata batang rokok yang dihisap sehari
dikalikan lama merokok dalam tahun.
Kuesioner Wawancara 0. Merokok
1. Tidak
merokok
Ordinal
6 Status Gizi Kondisi status gizi ibu menyusui saat
dilakukan penelitian. Diukur
berdasarkan rasio antara berat badan
(dalam kilogram) dengan tinggi badan
(dalam meter) pangkat dua dengan
rumus BB/TB2. Hasilnya dibandingkan
dengan Tabel standar nilai IMT
menurut Depkes, 2003.
Kuesioner, Timbangan
BB digital untuk
dewasa,microtoisedank
alkulator
Pengukuran
lansung
kg/m2 Ratio
7 Aktivitas
fisik
Jumlah aktifitas yang dilakukan ibu
minimal 10menit dalam satu kali
kegiatan yang meliputi pekerjaan
rumahtangga.
Kuesioner Tabel
penilaian
aktivitas
fisik
METs Ratio
88
No Variabel Definisi Alat Ukur Cara Ukur Hasil Ukur Skala
8 Suhu Tekanan udara yang ada di lingkungan
menyusui.
Mengukur Hygro meter °C Ratio
9 Kebisingan Dosispaparan kebisingan perhari yang
diperbolehkan dari tempat kerja (OHS,
2003dalam Umyati 2010).
Mengukur Sound
Level Meter
dB Ratio
10 Pencahayaan Sumber cahaya yang menerangi benda-
benda di tempatkerja (Budiono, dkk,
2003).
Mengukur Lux Meter Lux Ratio
89
3.2 Hipotesis
1. Ada hubungan antara faktor karakteristik individu (usia, kebiasaan merokok,
status gizi, aktivitasfisik) dengan kelelahan pada ibu menyusui ≤ 6 bulan di
Kelurahan Pisangan Ciputat Timur 2013.
2. Ada hubungan antara faktor karakteristik pekerjaan (risiko ergonomi postur
menyusui, lama menyusui dan lingkungan menyusui) dengan kelelahan pada
ibu menyusui ≤ 6 bulan di Kelurahan Pisangan Ciputat Timur 2013.
90
BAB IV
METODOLOGI PENELITIAN
4.1 Desain Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross
sectional (potong lintang) karena pada penelitian ini variabel independen dan
dependen akan diamati pada waktu (periode) yang sama.
4.2 Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2012 - Juli 2013 di Kelurahan
Pisangan Ciputat Timur.
4.3 Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi dan sampel penelitian ini adalah seluruh ibu menyusui ≤ 6 bulan
yang tidak bekerja di Kelurahan Pisangan Ciputat Timur berjumlah 38 orang.
4.4 Metode Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.
4.4.1 Data primer, adapun data yang dikumpulkan usia, kebiasaan merokok,
status gizi, lama menyusui, aktivitas fisik,lingkungan pekerjaan (suhu,
pencahayaan, dan kebisingan), perasaan kelelahan secara subjektif dan
objektif, serta tingkat resiko ergonomi posisi menyusui. Data usia,
91
kebiasaan merokok, status gizi, lama menyusui, aktivitas fisik dilakukan
dengan melakukan pengisian kuesioner. Data lingkungan pekerjaan
(suhu, pencahayaan dan kebisingan) dilakukan dengan pengukuran
menggunakan alat ukur. Data risiko ergonomi postur menyusui dilakukan
dengan cara melakukan observasi langsung serta wawancara pada ibu
menyusui di tempat penelitian.
Sedangkan untuk kelelahan kerja dilakukakan dengan Reaction Timer
Test yang merupakan alat untuk mengukur tingkat kelelahan berdasarkan
kecepatan waktu reaksi terhadap rangsangan cahaya.Prinsip kerja dari alat
ini adalah memberikan rangsangan tunggal berupa signal cahaya atau
lampu yang kemudian direspon secepatnya oleh tenaga kerja, kemudian
dapat dihitug waktu reaksi tenaga kerja yang mencatat waktu yang
dibutuhkan untuk merespon signal tersebut. Pengukuran dilakukan
sebanyak lima kali, setiap hasil pengukuran dijumlahkan, kemudian
diambil nilai rata-ratanya. Selain itu juga dilakukan wawancara terhadap
kuesioner skala Industrial Fatigue Research Commite (IFRC) untuk
mengetahui gejala kelelahan kelelahan kerja yang diukur pada saat
sebelum bekerja dan pada saat setelah bekerja.Hal ini dilakukan untuk
membandingkan pengukuran secara objektif dengan hasil pengukuran
subjektif, namun ketika ada ketimpangan dalam hasil pengukuran
keduanya maka pengukuran secara objektiflah yang nantinya diambil.
92
4.4.2 Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelusuran dokumen,
catatan, dan laporan dari posyandu. Seperti populasi ibu menyususi
dibawah enam bulan di kelurahan pisangan.
4.5 Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk pengumpulan data
(Notoatmodjo, 2002). Pada penelitian ini pengukuran variabel dilakukan dengan
menggunakan instrumen kuesioner yang terdiri dari bebrapa pertanyaan yang
berkaitan dengan variabel dependen dan independen. Pertanyaan dalam kuesioner
sesuai dengan variabel yang diteliti yaitu:
4.5.1 Pengukuran variabel kelelahan kerja secara objektif dilakukan
berdasarkan perhitungan reacion timer test yaitu hasil pengukuran
dibandingkan dengan standart pengukuran kelelahan kerja.
Tidak Lelah Waktu reaksi ≤240.0 milidetik.
Lelah Waktu reaksi >240.0milidetik .
Selain pengukuran secara subjektif juga dilakukan pengukuran
pembanding secara subjektif yaitu subjective self rating test dari
industrial fatigue research commite (IFRC) yang merupakan kuesioner
yang dapat untuk mengukur tingkat kelelahan subjektif yaitu pengukuran
yang mendukung hasil pengukuran subjektif yang dapat dilihat pada saat
wawancara. IFRC menggunakan sejumlah pertanyaan yang berhubungan
dengan gejala kelelahan. Skala ini mengandung 30 gejala kelelahan yang
dibuat dalam daftar pertanyaan. Jawaban dalam kuesioner tersebut dibagi
93
menjadi 4 bagian yaitu SS (Sangat Sering) dengan skor 4, S (Sering)
dengan skor 3, K (Kadang-kadang) dengan skor 2, dan TP (Tidak Pernah)
dengan skor 1. Skor yang diperoleh berkisar antara 1-60 tidak mengalami
kelelahan, 61-120 mengalami kelelahan.
4.5.2 Data usia diperoleh melalui wawancara kepada responden dengan
menggunakan instrumen kuesioner. Hasil yang didapat yaitu variabel
umur dalam tahun.
4.5.3 Lama menyusui diperoleh melalui wawancara kepada responden dengan
menggunakan instrumen kuesioner. Hasil yang didapat yaitu total lama
ibu menyusui dalam sehari.
4.5.4 Kebiasaan merokok, kesegaran jasmani diperoleh melalui wawancara
kepada responden dengan menggunakan instrumen kuesioner.
4.5.5 Variabel aktivitas fisik
Aktvitas fisik diukur dengan menggunakan kuesioner IPAQ long
forms yang berkaitan dengan aktivitas pekerjaan rumah tangga yang
dilakukan minimal 10 menit dalam 1 kali kegiatan yang merupakan
aktivitas fisik harian berdasarkan level intensitas.
Level MET setiap intensitas adalah berjalan sebanyak 3.3 METs,
aktivitas sedang sebanyak 4.0 METs, dan aktivitas keras sebanyak 8.0
METs. Total aktivitas fisik atau total MET/menit-minggu dihitung
dengan:
94
Berjalan (MET x menit x hari) + Sedang (MET x menit x hari) +
Keras (MET x menit x hari).
Kemudian total aktivitas fisik tersebut disesuaikan dengan kategori di
bawah ini (IPAQ, 2005) :
1. Ringan
Merupakan level terendah dalam aktivitas fisik. Seseorang yang
termasuk ke dalam kategori ini adalah apabila tidak melakukan
aktivitas fisik apapun atau tidak memenuhi kriteria aktivitas fisik
sedang dan berat.
2. Sedang
Dikatakan termasuk dalam aktivitas fisik sedang jika memenuhi
kriteria berikut:
a. Melakukan aktivitas fisik dengan intensitas kuat minimal 20
menit selama 3 hari atau lebih,
b. Atau melakukan aktivitas fisik dengan intenistas sedang selama
minimal 5 hari dan atau berjalan minimal 30 menit setiap hari,
atau kombinasi berjalan, aktivitas fisik dengan intenistas sedang
atau keras selama 5 hari atau lebih yang menghasilkan total
aktivitas fisik dengan minimal 600 MET-menit/minggu.
95
3. Berat
Dikatakan termasuk dalam aktivitas fisik berat jika memenuhi
kriteria berikut:
a. Melakukan aktivitas fisik dengan intensitas keras selama 3 hari atau
lebih yang menghasilkan total aktivitas fisik minimal sebanyak 1500
MET-menit/minggu,
b. atau jika melakukan kombinasi berjalan, aktivitas fisik dengan
intenistas keras atau kuat selama 7 hari atau lebih yang menghasilkan
total aktivitas fisik minimal sebanyak 3000 METmenit/minggu.
4.5.6 Pengukuran variabel satus gizi dengan pengukuran berat badan dan tinggi
badan dengan menggunakan timbangan digital dan mikrotoa. Kemudian
tahap selanjutnya adalah menghitung nilai IMT yaitu dengan rumus:
Kategori berat badan menurut IMT :
1.Berisiko ( <17,0-18,4 dan 25,1- ≥ 27,0)
2.Tidak berisiko(18.5-25,0)
a) Data berat badan
Data mengenai berat badan diperoleh dengan cara melakukan
penimbangan berat badan langsung menggunakan timbangan badan
Berat badan (kg)
IMT =
Tinggi badan (m) x Tinggi badan (m)
96
pada saat seblum beraktifitas. Langkah-langkah pengukuran gtersebut
adalah:
- Pastikan jarum pada dispali ada pada posisi nol
- Lepaskan sepatu atau alas kaki lainnya
- Berdiri diatas timbangan
- Baca hasil pada display yang ditunjjukkan oleh jarum metal.
b) Data tinggi badan
Data tinggi badan diperoleh melalui pengukuran tinggi badan langsung
menggunakan microtoise/alat pengukur tinggi badan.Kemudian catat
hasil pengukurannya.
4.5.7 Pengukuran variabel risiko ergonomi postur ibu menyusui: setelah
dilakukan observasi dengan pengambilan video menggunakan kamera
pada posisi menyusui kemudian diukur menggunakan busur dengan
menggunakan metode RULA dari masing-masing postur tubuh. Adapun
tahapan-tahapannya sebagai berikut
1. Mengobservasi postur menyusui dan menentukan nilai untuk
kelompok postur A sesuai dengan kriteria penilaian RULA yang terdiri
dari anggota tubuh:
a. lengan atas dengan skor yaitu:
1) Skor 1 = 20° ekstensi - 20° fleksi
2) Skor 2 = >200° ekstensi – 200- 450° fleksi
3) Skor 3 = 450-900
97
4) Skor 4 = >900
Skor +1 jika: bahu terangkat, atau lengan atas abduksi, dan -1 jika
lengan bawah disangga
b. Lengan bawah dengan skor yaitu:
1) Skor 1 = 60° -100°
2) Skor 2 = 0°-60° atau > 100°
Skor +1 jika lengan bawah menyilang ke garis tengah tubuh
(mideline) atau keluar
c. Pergelangan tangan dengan skor yaitu:
1) Skor 1 = 0°
2) Skor 2 = 0-15° fleksi atau ekstensi
3) Skor 3 = >15° fleksi atau ekstensi
Skor + 1 jika terjadi deviasi ulnar atau radial
d. Perputaran pergelangan tangan dengan skor yaitu:
1) Skor 1 = berputar kedalam
2) Skor 2 = berputar keluar
2. Memasukkan masing-masing nilai sekor untuk kelompok postur A yaitu
lengan atas, lengan bawah, dan pergelagan tangan, ke table A untuk
mengetahui skor postur A
3. Mengobservasi dan menentukan nilai penggunaan otot untuk kelompok
postur B sesuai dengan kriteria penilaian RULA dengan skor yaitu:
98
a. Skor 0 = dinamis, jika postur ditahan <1 menit atau jika gerakan
berulang kurang dari 4 kali permanit
b. Skor 1 = statis, jika postur ditahan >1 menit atau jika gerakan
berulang lebih dari 4 kali permenit.
4. Mengobservasi dan menentukan nilai beban untuk kelompok postur A
sesuai dengan kriteria penilaian RULA dengan skor yaitu:
a. Skor 0 = tidak ada beban atau berat beban <2kg secara intermittent
b. Skor 1 = berat beban 2-10 kg secara intermittent
c. Skor 2 = berat beban 2-10 kg secara statis atau berulang-ulang, atau
berat beban 10 kg atau lebih secara intermittent
d. Skor 3 = berat beban 10 kg statis atau berulang-ulang, atau gerakan
cepat (shock)
5. Menjumlahkan nilai skor kelompok postur A, dengan penggunaan otot,
dan beban untuk mengetahui skor A.
a. Memasukkan hasil skor A ketabel C, pada bagian kolom pertama
skor pergelangan tangan dan tangan, kemudian
b. Mengobservasi postur pekerja dan menentukan nilai untuk kelompok
postur B sesuai dengan kriteria penilaian RULA yang terdiri dari
anggota tubuh:
1) Leher dengan skor yaitu:
a) Skor 1 = 0-10°
b) Skor 2 = 10°-20°
99
c) Skor 3 = >20°
d) Skor 4 = ekstensi
Skor +1 jika leher berputar atau miring kesamping
2) Punggung dengan skor yaitu:
a) Skor 1 = 0-10°
b) Skor 2 = 10°-20°
c) Skor 3 = 20°-60°
d) Skor 4 = >60°
3) Kaki dengan skor yaitu:
a) Skor 1 = kaki yang disangga dan seimbang
b) Skor 2 = jika kaki tidak disangga dan tidak seimbang
6. Memasukkan masing-masing nilai skor untuk kelompok postur B yaitu
leher, punggung, dan kaki kedalam table B unuk mengetahui skor postur
B.
7. Mengobservasi dan menentukan nilai penggunaan otot untuk kelompok B
sesuai dengan kriteria penilaian RULA dengan skor yaitu:
a. Skor 0 = dinamis, jika postur ditahan <1 menit atau jika gerakan
berulang kurang dari 4 kali permenit
b. Skor 1 = statis, jika postur ditahan >1 menit atau jika gerakan
berulang lebih dari 4 kali permenit.
8. Mengobservasi dan menentukan nilai beban untuk kelompok B sesuai
dengan kriteria penilaian RULA dengan skor yaitu:
100
a. Skor 0 = tidak ada beban atau berat beban < 2 kg secara intermitten
b. Skor 1 = berat beban 2-10 kg secara intermitten
c. Skor 2 = berat beban 2-10 kg secara statis atau berulang-ulang, atau
berat beban 10 kg atau lebih secara intermitten
d. Skor 3 = berat beban 10 kg statis atau berulang-ulang, atau gerakan
cepat (shock).
9. Menjumlahkan nilai skor kelompok postur B, dengan menggunakan otot
dan beban, untuk mengetahui skor B.
10. Memasukkan hasil nilai skor B ke dalam table C, pada bagian baris
pertama skor leher, punggung, dan kaki.
11. Menentukan nilai skor final dengan menarik garis mendatar dari kolom
skor A dengan baris skor B dalam table C untuk mendapatkan nilai skor
final RULA.
12. Setelah mendapatkan nilai skor final, masukkan nilai pada kategori risiko
(action level) untuk menegetahui tingkat risikonya serta level perubahan.
Table 4.3
Skor final RULA
Nilai Skor RULA Action Level Level Perubahan
1-2 1 Dapat diterima
3-4 2 Investigasi lebih lanjut, mungkin
butuh perubahan
5-6 3 Investigasi lanjut, perubahan segera
7 4 Investigasi, menerapka perubahan
101
4.5.8 Pengukuran variabel suhu dengan menggunakan Termometer yaitu
dengan meletakkan termometer di tempat biasanya ibu menyusui, tunggu
hingga stabil.
4.5.9 Pengukuran variabel pencahayaan dengan menggunakan Lux meter.
Penggunaan alat ini yang harus benar-benar diperhatikan adalah alat
sensornya,karena sensornyalah yang akan mengukur kekuatan
penerangan suatu cahaya. Oleh karena itu sensor harus ditempatkan pada
daerah yang akan diukur tingkat kekuatan cahayanya (iluminasi) secara
tepat agar hasil yang ditampilkan pun akuarat.
Adapun prosedur penggunaan alat ini adalah sebagai berikut :
a) Geser tombol ”off/on” kearah On.
b) Pilih kisaran range yang akan diukur ( 2.000 lux, 20.000 lux atau
50.000 lux) pada tombol Range.
c) Arahkan sensor cahaya dengan menggunakan tangan pada permukaan
daerah yang akan diukur kuat penerangannya.
d) Lihat hasil pengukuran pada layar panel.
4.5.10 Pengukuran variabel kebisingan dengan menggunakan Sound Level
Meter. Adapun operasional pengukuran dapat dilakukan sebagai berikut.
a) Penentuan staindar yang akan diacu dalam survei.
102
b) Pemeriksaan instrumen. Hal ini meliputi pemeriksaan batere SLM dan
kaliberator, serta aksesories misalnya windscreen, rain cover, dan lain-
lain.
c) Kalibrasi instrumen dilakukan selama 1 menit sebelum dan sesudah
pengukuran berlangsung.
d) Pembuatan denah lokasi dan titik dimana pengukuran dilakukan yaitu
di tempat biasanya ibu menyusui.
e) Bila pengukuran dilakukan dengan free-field microphone (standar
IEC) maka SLM diarahkan lurus kesumber. Sedangkan jika mikropon
yang digunakan merupakan rendom incidence microphone (ANSI),
maka SLM harus diorientasikan sekitar 70˚-80˚ terhadap sumber
bising.
f) Dalam keadaan kebisingan berasal dari lebih dari satu arah, maka
sangat penting untuk memilih mikropon dan mounting yang tepat yang
memungkinkan untuk mencapai karakteristik omnidirectional terbaik.
g) Pemilihan weighting network yang sesuai.
h) Pemilihan respons detektor yang sesuai, F atau S untuk mendapatkan
pembacaan yang akurat.
i) Hindarkan refleksi baik dari tubuh operator maupun bloking suara dari
arah tertentu.
j) Saat pengukuran langsung, selalu perhatikan hal-hal berikut:
- Hindari pengukuran dekat bidang pemantul
103
- Lakukan pengukuran pada jarak yang tepat, sesuai dengan standart
baku mutu yang diacu
- Cek bising latar
- Pastikan tidak dapat perintang terhadap sumber bising yang diukur
- Selalu gunakan windshield (windscreen), dan
- Tolak pembacaan overloud.
4.6 Pengolahan Data
Pada proses pengolahan data terbagi menjadi tiga jenis pengolahan data yaitu
pengolahan variabel postur menyususi dengan metode RULA, variabel usia,
kebiasaan merokok, status gizi,lama menyusui,aktivitas fisik, perasaan kelelahan
secara subjektif dari hasil penyebaran kuesioner,variabel kelelahan secara objektif
dan kondisi lingkungan pekerjaan (suhu, kebisingan dan pencahayaan) dengan
melakukan pengukuran. Seluruh data yang terkumpul baik data primer maupun
data sekunder akan diolah melalui tahap-tahap sebagai berikut:
4.6.1 Mengkode data (data coding)
Kegiatan ini merupakan proses pendeskripsian data dan pemberian kode
pada jawaban responden, dilakukan pada pembuatan kuesioner untuk
mempermudah proses pemasukan dan pengolahan data selanjutnya.
4.6.2 Menyunting data (data editing)
104
Dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran data seperti
kelengkapan pengisian, kesalahan pengisian, konsistensi pengisian setiap
jawaban kuesioner. Pemeriksaan ini dilakukan pada saat dilapangan.
4.6.3 Memasukkan data (data entry)
Memasukkan data dalam program software computer berdasarkan
klasifikasi dan variabel yang akan dianalisis.
4.6.4 Membersihkan data (data cleaning)
Pengecekan kembali data yang telah dimasukkan untuk memastikan data
tersebut tidak ada yang salah, sehingga dengan demikian data tersebut telah
siap diolah dan dianalisis.
4.7 Analisis Data
4.7.1 Analisis Univariat
Analisis yang dilakukan untuk melihat distribusi frekuensi dan persentase
dari setiap variabel independen dan dependen yang dikehendaki dari tabel
distribusi.
4.7.2 Analisis Bivariat
Analisis yang dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel
independen dan dependen dengan melakukan uji man-Whitney dan uji Chi
Square . Uji Mann-Whitney U digunakan untuk setiap kasus yang memiliki
skor pada dua variabel, variabel pengelompokan (variabel independen atau
kategoris) dan variabel tes (variabel dependen atau kuantitatif). Variabel
105
dependen dalam penelitian ini adalah kelelahan dan variabel dependen
dalam penelitian ini adalah variabel postur menyususi, variabel usia,
kebiasaan merokok, status gizi, lama menyusui, dan aktivitas fisik, untuk
variabel kebiasaan merokok dalam penelitian ini menggunakan uji
ChiSquare untuk menghubungkan variabel kategorik dan kategorik.
Variabel yang termasuk pada uji Chi Square yaitu variabel kebiasaan
merokok yang akan dihubungkan dengan variabel kelelahan dengan batas
kemaknaan P value ≤ 0,05 berarti ada hubungan yang bermakna secara
statistik dan P value> 0,05 berarti tidak ada hubungan yang bermakna
secara statistik (Apriani, 2003).
106
BAB V
HASIL
5.1. Analisis Univariat Pada analisis univariat ini akan digambarkan distribusi frekuensi dari
masing-masing variabel yang diteliti baik variable independen maupun variable
dependen.
5.1.1. Gambaran Kelelahan pada Ibu Menyusui ≤ 6 Bulan di Kelurahan
Pisangan Ciputat Timur 2013
Variabel kelelahan diukur dengan Reaction Timer Test yang
merupakan alat untuk mengukur tingkat kelelahan berdasarkan
kecepatan waktu reaksi terhadap rangsangan cahaya . Dalam analisis
data,kelelahan di kelompokkan menjadi dua kategori lelah
(waktureaksi>240.0 milidetik) dan tidak lelah (waktureaksi< 240.0
milidetik) Gambaran kelelahan posisi duduk ibu saat menyusui dengan
indikator Reaction Timer Test adalah sebagai berikut:
Tabel 5.1
Gambaran Distribusi Kelelahan pada Ibu Menyusui ≤ 6 Bulan di
Kelurahan Pisangan Ciputat Timur 2013
Variabel Kategori Jumlah Persentase %
kelelahan Lelah
TidakLelah
35
3
92.1
7.9
Sumber : Data Primer Tahun 2013
107
Berdasarkan pengumpulan data dengan Reaction Timer Test
terdapat 92.1% ibu menyusui mengalami kelelahan.
Selain menggunakan Reaction Timer Test, variable kelelahan
juga diukur dengan menggunakan Subjective Syimtoms Test (SST) yang
berisi sejumlah pertanyaan yang berhubugan dengan gejala-gejala
kelelahan. Skala IFRC ini terdapat 30 gejala kelelahan yang disusun
dalam bentuk daftar pertanyaan. Hal ini di lakukan sebagai pembanding
antara pengukuran yang bersifat objektif dan subjektif.
Adapun gambaran kelelahan posisi duduk ibu saat menyusui
dengan indikator Subjective Syimtoms Test adalah sebagai berikut:
Tabel 5.2
Gambaran Distribusi Kelelahan pada Ibu Menyusui ≤ 6 Bulan di
Kelurahan Pisangan Ciputat Timur 2013
Variabel Kategori Jumlah Persentase %
kelelahan Lelah
TidakLelah
34
4
89.5
10.5
Sumber : Data Primer Tahun 2013
Berdasarkan pengumpulan data dengan pengukuran Subjective
Syimtoms Test terdapat 89.5% ibu menyusui mengalami kelelahan.
108
5.1.2. Gambaran Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya
Kelelahan pada Ibu Menyusui ≤ 6 Bulan di Kelurahan Pisangan
Ciputat Timur 2013.
Variabel risiko postur menyusui diukur dengan menggunakan
metode RULA Dalam melakukan pengukuran metode RULA mernbagi
bagian tubuh menjadi dua grup yaitu grup A dan B. Grup A meliputi
bagian lengan atas dan bawah, serta pergelangan tangan. Sementara
grup B meliputi Ieher, punggung, dan kaki. Hal ini untuk memastikan
bahwa seluruh postur tubuh terekam, sehingga segala kejanggalan atau
batasan postur oleh kaki, punggung atau Ieher yang mungkin saja
mempengaruhi postur anggota tubuh bagian atas dapat tercakup dalam
penilaian dengan penentuan skor 1 sampai dengan 7.
Variabel usia diukur melalui wawancara kepada responden
dengan menggunakan instrumen kuesioner dan hasil yang didapat yaitu
variabel umur dalam tahun. variabel kebiasaan merokok, kesegaran
jasmani diperoleh melalui wawancara kepada responden dengan
menggunakan instrumen kuesioner. Variabel status gizi diperoleh
dengan pengukuran berat badan dan tinggi badan dengan menggunakan
timbangan digital dan mikrotoa.
Gambaran faktor–faktor yang menpengaruhi kelelahan (risiko
ergonomi postur menyusui, usia, kebiasaan merokok, status gizi, lama
menyusui, aktivitas fisik, suhu, kebisingan dan pencahayaan) pada ibu
109
menyusui ≤ 6 bulan di Kelurahan Pisangan Ciputat Timur 2013 dapat
dilihat pada tabel 5.3.
Tabel 5.2
Gambaran Distribusi Responden Berdasarkan Faktor-Faktor yang
Menyebabkan Terjadinya Kelelahan pada Ibu Menyusui ≤ 6
Bulan di Kelurahan Pisangan Ciputat Timur 2013.
Variabel Mean Median Std. Deviasi Minimum Maksimum
1. Faktor Individu
Usia Ibu (tahun) 27.34 25.50 6.248 18 43
Status Gizi (kg/m2) 25.3013 24.4000 5.18823 16.59 40.49
Aktivitasfisik (METs) 19015.15 17136 19342.72 1465.50 96390
2. Faktor Pekerjaan
Risiko Ergonomi
Postur Menyusui
6.84 7.00 0.370 6 7
Kebisingan (dB) 66.837 66.300 4.3113 60.6 81.4
Cahaya (lux) 130.050 64.750 1.8012 12.0 803.0
Suhu (oC) 32.566 32.000 1.7675 30.0 37.0
Lama Menyusui
(menit)
183.92 99 176.90 25 900
Sumber : Data Primer Tahun 2013
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai mean faktor
individu yaitu variable usia ibu adalah 27.34 tahun dengan nilai
minimum 18 tahun dan nilai maksimum 43 tahun. Karena variable usia
ibu homogen maka tidak dilakukan analisis lebih lanjut. Sedangkan
untuk status gizi nilai mean adalah 25.3013 kg/m2
dengan nilai
minimum 16.59 kg/m2
dan maksimum 40.49 kg/m2
dan nilai mean
variable aktivitas fisik ibu menyusui ≤ 6 bulan adalah 19015.15 METs,
dengan nilai minimum 1465.50 METs, dan maksimum 96390 METs
110
Sedangkan nilai mean foktor pekerjaan, yaitu faktor tingkat
risiko ergonomi postur menyusui adalah 6.84 dengan nilai minimum 6
dan maksimum 7, untuk nilai mean kebisingan 66.837 dB dengan nilai
minimum 60,6 dB dan maksimum 81.4 dB. Nilai mean pencahayaan
adalah 130.050 lux dengan nilai minimum 12.0 lux dan nilai maksimum
803.0 lux. Nilai mean suhu adalah 32.566oC dengan nilai minimum
30.0oC dan maksimum 37.0
oC. Sedangkan untuk variabel lama
menyusui ibu nilai meannya adalah 183.92 dengan nilai minimum 25
dan nilai maksimum 900.
Tabel 5.3
Gambaran Distribusi Responden Berdasarkan
FaktorKebiasaanMerokokpadaIbuMenyusui ≤ 6 Bulan di
KelurahanPisanganCiputatTimur2013
Variabel Kategori Jumlah Persentase %
Kebiasaanmerokok Merokok
TidakMerokok
1
37
2,6
97,4
Sumber : Data Primer Tahun 2013
Dari tabel diatas terlihat bahwa ibu yang tidak merokok yang
paling banyak dengan nilai 97,4 %. Karena variable kebiasaan merokok
homogeny maka tidak dilakukan analisis lebih lanjut.
111
5.2. Analisis Bivariat
5.2.1. Hubungan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya
Kelelahan pada Ibu Menyusui ≤ 6 Bulan di Kelurahan Pisangan
Ciputat Timur 2013
Hubungan antara risiko ergonomi postur menyusui, usia, status
gizi, lama menyusui, aktivitas fisik, suhu, kebisingan, pencahayaan
dengan kelelahan pada ibu menyusui ≤ 6 bulan adalah sebagai berikut:
Tabel 5.4
Hubungan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya
Kelelahan pada Ibu Menyusui ≤ 6 Bulan di Kelurahan Pisangan
Ciputat Timur 2013.
Variabel N Mean
Rank
Mann-
Whitney U
P-
value
1.Faktor Individu
Usia Lelah 35 18.60 21.000 0.087
Tidaklelah 3 30.00
Status Gizi Lelah 35 18.67 44.000 0,645
Tidaklelah 3 29.67
AktivitasFisik Lelah 35 17.77 25.500 0,168
Tidaklelah 3 29.67
2.Faktor Pekerjaan
Risiko
ErgonomiPosturMenyusui
Lelah 35 19,29 43.000 0.441
Tidaklelah 3 22.50
Lama Menyusui Lelah 35 18.54 19.000 0,063
Tidaklelah 3 30.67
Suhu Lelah 35 19.46 51.000 0,934
Tidaklelah 3 20.00
Kebisingan Lelah 35 18.73 25.500 0.144
Tidaklelah 3 28.50
Pencahayaan Lelah 35 19.74 44.000 0.645
Tidaklelah 3 16.67
Sumber : Data Primer Tahun 2013
112
Berdasarkan perhitungan diatas dapat dilihat bahwa nilai mean
untuk ibu menyusui yang mengalami kelelahan lebih kecil dari pada
yang tidak mengalami kelelahan (18.60<30.00) dengan nilai P-value
0,087 yang lebih besar dari 0,05. Hal tersebut dapat disimpulkan tidak
ada hubungan antara usia ibu dengan terjadinya kelelahan.
Variabel status gizi berdasarkan perhitungan diatas dapat dilihat
bahwa nilai mean untuk ibu menyusui yang mengalami kelelahan lebih
besar dari pada yang tidak mengalami kelelahan (19.74>16.67) dengan
nilai P-value 0,645 yang lebih besar dari 0,05. Hal tersebut dapat
disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara status gizi ibu dengan
terjadinya kelelahan.
Variabel aktivitas fisik berdasarkan perhitungan diatas dapat
dilihat bahwa nilai mean untuk ibu menyusui yang mengalami
kelelahan lebih kecil dari pada yang tidak mengalami kelelahan
(17.77<26.50) dengan nilai P-value 0,168 yang lebih besar dari 0,05.
Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara
aktivitas fisik dengan terjadinya kelelahan.
Variabel risiko ergonomi postur menyusui berdasarkan
perhitungan diatas dapat dilihat nilai mean untuk ibu menyusui yang
mengalami kelelahan lebih kecil dari pada yang tidak mengalami
kelelahan (19,29 <22.50) dengan nilai P-value0,441 yang lebih besar
113
dari 0,05. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan
antara postur menyusui denganterjadinya
Variabel lama menyusui berdasarkan perhitungan diatas dapat
dilihat bahwa nilai mean untuk ibu menyusui yang mengalami
kelelahan lebih kecil dari pada yang tidak mengalami kelelahan
(18.54<30.67) dengan nilai P-value 0,063 yang lebih besar dari 0,05.
Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara lama
menyusui dengan terjadinya kelelahan.
Variabel suhu berdasarkan perhitungan diatas dapat dilihat
bahwa nilai mean untuk ibu menyusui yang mengalami kelelahan lebih
kecil dari pada yang tidak mengalami kelelahan (19.47<20.00) dengan
nilai P-value 0,934 yang lebih besar dari 0,05. Hal tersebut dapat
disimpulkan bahwa tidak ada hubungana ntara suhu dengan terjadinya
kelelahan.
Variabel kebisingan berdasarkan perhitungan di atas dapat dilihat
bahwa nilai mean untuk ibu menyusui yang mengalami kelelahan lebih
kecil dari pada yang tidak mengalami kelelahan (18.73<28.50) dengan
nilai P-value 0,144 yang lebih besar dari 0,05. Hal tersebut dapat
disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara kebisingan dengan
terjadinya kelelahan.
Variabel pencahayaan berdasarkan perhitungan di atas dapat
dilihat bahwa nilai mean untuk ibu menyusui yang mengalami
114
kelelahan lebih besar dari pada yang tidak mengalami kelelahan
(19.74>16.67) dengan nilai P-value 0,645 yang lebih besar dari
0,05.Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara
pencahayaan dengan terjadinya kelelahan.
115
BAB VI
PEMBAHASAN
6.1. Keterbatasan Penelitian
a. Data kelelahan diukur dengan Reaction Timer Test . Sehingga responden
yang masih awam menekan klik kanan pada mouse mempengaruhi
pemanjangan waktu reaksi yang merupakan petunjuk adanya perlambatan
pada proses faal syaraf otot. sehingga mungkin saja terjadi bias.
b. Ketika dilakukan pengambilan video oleh pengumpul data, seringkali ibu
tidak berada pada sikap duduk alami saat menyusui.
6.2. Gambaran Kelelahan pada Ibu Menyusui ≤ 6 Bulan di Kelurahan Pisangan
Ciputat Timur 2013
Menyusui merupakan kegiatan yang dilakukan selama berjam-jam dan
berkali-kali setiap harinya oleh ibu pasca melahirkan. Disebutkan juga dalam
buku An Easy Guide to Breastfeeding bahwa menyusui dilakukan minimal 2
jam sekali, namun waktu menyusui ini tidak boleh dijadwal secara ketat karena
semakin sering bayi menyusu, maka akan menstimulasi payudara ibu untuk
memproduksi lebih banyak ASI. Sehingga kegiatan menyusui juga bisa disebut
kegiatan yang bersifat incidental yang membutuhkan kesabaran dan tenaga .
Satu gejala yang sering dilaporkan ibu yang baru pertama kali menyusui
bayinya yang membuat ibu memperpendek lamanya dalam menyusui adalah
116
kelelahan (fatigue) (Chapman,1998 dalam Rohman, 2012). Kelelahan yang
dirasakan oleh ibu-ibu selama menyusui menurunkan produksi ASI selama bulan
pertama postpartum dan menjadi faktor yang utama untuk menyapih bayinya
(Rohman, 2012). Kelelahan ini terjadi dimungkinkan karena postur yang
digunakan ibu yang menuntut beberapa bagian tubuh dalam kondisi postur
janggal. Selain faktor postur yang digunakan ketidaktentuan waktu menyusi juga
berisiko menimbulkan kelelahan hal ini sejalan dengan pendapatnya Manuaba
(1990) dalam Virgy (2011) menjelaskan bahwa jam kerja berlebihan, jam kerja
lembur diluar batas kemampuan akan mempercepat timbulnya kelelahan. Serta
beberapa faktor lain yang berisiko terjadinya kelelahan seperti lingkungan kerja
maupun karakteristik pekerja dalam hal ini adalah ibu menyusui.
Kelelahan adalah suatu mekanisme perlindungan tubuh agar tubuh
menghindari kerusakan lebih lanjut, sehingga dengan demikian terjadilah
pemulihan (Suma’mur, 1989). Rizeddin (2000) dalam Nurhidayati (2009)
menyatakan kelelahan menurunkan kapasitas kerja dan ketahanan kerja yang
ditandai oleh sensasi lelah, motivasi menurun, aktivitas menurun. Menurut
Grandjean (1997) dalam Virgy (2011) kelelahan kerja merupakan gejala yang
ditandai adanya perasaan lelah dan kita akan merasa segan dan aktifitas akan
melemah serta ketidakseimbangan. Selain itu, keinginan untuk berusaha
melakukan kegiatan fisik dan mental akan berkurang karena disertai perasaan
berat, pening, capek. Istilah kelelahan menunjukkan kondisi yang berbeda-beda
117
dari setiap individu, tetapi semuanya bermuara pada kehilangan efisiensi dan
penurunan kapasitas kerja serta ketahanan tubuh (Tarwaka et al, 2004).
Pengukuran kelelahan kerja melibatkan fungsi persepsi, interpretasi dan
reaksi motor. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan pengukuran
waktu reaksi. Waktu reaksi adalah jangka waktu dari pemberian suatu
rangsangan sampai kepada suatu saat kesadaran atau dilaksanakan kegiatan.
Dalam uji waktu reaksi dapat digunakan nyala lampu, denting suara, sentuhan
kulit atau goyangan badan. Pada metode yang dilakukakan menggunakan
Reaction Timer Test dengan nyala lampu. terjadinya pemanjangan waktu reaksi
merupakan petunjuk adanya perlambatan pada proses faal syaraf dan otot.
Hasil dari analisis univariat berdasarkan pengumpulan data dengan
Reaction Timer Test terdapat 92.1% ibu menyusui mengalami kelelahan.
Selain itu didukung dengan pengukuran menggunakan Subjective Syimtoms
Test (SST) yang berisi sejumlah pertanyaan yang berhubugan dengan gejala-
gejala kelelahan. Dari hasil pengukuran tersebut terdapat 89.5% ibu menyusui
mengalami kelelahan. Hal ini bisa terjadi dimungkinkan karena menyusui
dilakukan minimal 2 jam sekali dan bayi tidak diposisikan pada payudara
secara tepat yang meneyebabkan pembunggukan pada punggung. Selain itu
berat badan bayi juga mempengaruhi pembebanan pada lengan tangan ibu,
sehingga lengan tangan dituntut untuk menyangga dengan posisi statis selama
118
menyusui. Hal ini bisa dimungkinkan menjadi penyebab terjadinya kelelahan
pada ibu menyusui.
Sehingga diperlukan tindakan lebih lanjut, karena kelelahan yang
dirasakan oleh ibu selama menyusui menurunkan produksi ASI selama bulan
pertama postpartum dan menjadi faktor yang utama untuk menyapih bayinya
sehingga risiko pemenuhan ASI kepada bayi kurang terpenuhi. Ada beberapa
hal yang bisa dilakukan ibu untuk mengurangi terjadinya kelelahan saat
menyusui yaitu ibu memilih posisi paling nyaman yang dirasakan baik ibu dan
bayinya saat menyusui berlangsung dan menggunakan alat bantu seperti bantal
untuk menyangga dan menyesuaikan perletakan putting dan bayinya, selain itu
juga bisa menggunakan kursi yang ergonomis yang didesain kkkhusus untuk
ibu menyusui.
6.3. Analisis Faktor Karakteristik Individu (Usia, Status Gizi, Aktivitas Fisik)
pada Ibu Menyusui ≤ 6 Bulan di Kelurahan Pisangan Ciputat Timur 2013.
6.3.1. Hubungan Usia dengan Kelelahan
Menurut Setyawati (1994) yang dikutip oleh Silastuti (2006)
faktor individu seperti umur juga dapat berpengaruh terhadap waktu
reaksi dan perasaan lelah tenaga kerja. Pada umur yang lebih tua terjadi
penurunan kekuatan otot, tetapi keadaan ini diimbangi dengan stabilitas
emosi yang lebih baik dibanding tenaga kerja yang berumur muda yang
dapat berakibat positif dalam melakukan pekerjaan. Menurut Akerstedt et
119
al (2002) dalam Dewi (2006) bahwa kelelahan lebih cenderung terjadi
pada pekerja berumur kurang lebih sama dengan 49 tahun.
Hasil dari analisis univariat bahwa rata-rata usia ibu adalah 27
tahun dengan nilai minimum 18 tahun dan nilai maksimum 43 tahun.
Hasil analisis hubungan antara usia dengan kelelahan pada ibu menyusui
dibawah enam bulan di Kelurahan Pisangan Ciputat Timur 2013dengan
nilai signifikan 95% diperoleh bahwa nilai Mean Rank untuk ibu
menyusui yang mengalami kelelahan 18.60 dengan nilai P-value
sebesar 0,087 yang lebih besar dari 0,05, hal tersebut dapat disimpulkan
tidak ada hubungan antara usia ibu dengan terjadinya kelelahan. Hal ini
sejalan dengan penelitian Dewi (2006) yang menyatakan tidak adanya
hubungan antara usia dengan kelelahan kerja. Namun tidak sejalan
dengan penelitian yang dilakukan oleh J Hum lact University of Kansas
School of Nursing, Kansas City 66160-7502, Amerika Serikat (1998)
yang menyatakan bahwa usia ibu berkorelasi positif dengan kelelahan.
Hal ini kemungkinan disebabkan karena rata-rata usia ibu menyusui
dibawah 40 tahun. Sesuai dengan teori Hidayat (2003) mendapatkan bukti
di Negara Jepang menunjukkan bahwa pekerja yang berusia 40-50 tahun
akan lebih cepat menderita kekelahan kerja dibandingkan dengan pekerja
relative lebih muda.
120
6.3.2. Hubungan antara Status Gizi dengan Kelelahan
Status gizi merupakan salah satu unsur yang menentukan kualitas
fisik dan kondisi fisik tenaga kerja sehingga berpengaruh terhadap
terjadinya kelelahan (Wignjosoebroto, 2003 dalam Virgy, 2011).
Berat badan yang kurang ideal baik itu kurang ataupun kelebihan
dapat menimbulkan kerugian. Orang yang mempunyai kelebihan berat
badan (gemuk) juga akan mudah mengalami kelelahan karena, menurut
Almatsier (2004) orang yang gemuk membutuhkan jumlah energi yang
lebih besar untuk membawa tubuhnya, seiring dengan kenaikan berat
badannya. Sehingga apabila orang yang mempunyai kelebihan berat
badan dibebani dengan beban yang lain, maka akan lebih besar lagi
jumlah energy yang dibutuhkannya. Masalah kekurangan atau kelebihan
gizi pada orang dewasa (usia 18 tahun ke atas) merupakan masalah
penting, karena selain mempunyai resiko penyakit tertentu, juga dapat
mempengaruhi produktivitas kerja.
Status gizi orang dewasa diukur menggunakan IMT, Karena
responden dalam penelitian ini adalah ibu menyusui yang kesemuanya
berusia lebih dari 18 tahun keatas. Menurut Pekik (2006) dalam Kasanah
(2011) menyatakan bahwa Indeks Masa Tubuh (IMT) mempunyai
121
beberapa kelebihan yaitu pengukuran sederhana dan mudah serta
menentukan kelebihan dan kekurangan berat badan.
Hasil dari analisis univariat bahwa rata-rata status gizi ibu
menyusui dibawah enam bulan adalah 25.3013 dengan nilai minimum
16.59 dan maksimum 40.49 hal ini menunjukkan bahwa rata-rata status
gizi ibu menyusui dibawah enam bulan termasuk kategori kelebihan
berat badan tingkat ringan. Hal ini terjadi dimungkinkan karena faktor
pasca melahirkan.
Hasil analisis hubungan antara status gizi dengan kelelahan pada
ibu menyusui dibawah enam bulan di Kelurahan Pisangan Ciputat Timur
2013 dengan nilai signifikan 95% diperoleh bahwa nilai Mean Rank
untuk ibu menyusui yang mengalami kelelahan sebesar 19.74 dengan
nilai P-value sebesar 0,645 yang lebih besar dari 0,05, hal tersebut dapat
disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara status gizi ibu dengan
terjadinya kelelahan. Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang
dilakukan oleh Eraliesa (2008) yang menyatakan bahwa terdapat
hubungan antara status gizi dengan tingkat kelelahan.
Menurut Wignjosoebroto, 2003 dalam Virgy, 2011 menyatakan
bahwa status gizi merupakan salah satu unsur yang menentukan kualitas
fisik dan kondisi fisik tenaga kerja sehingga berpengaruh terhadap
122
terjadinya kelelahan namun pada hasil penelitian kali ini diperoleh hasil
yang berbeda. Ketidaksesuaian tersebut dapat di mungkinkan adanya
faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini yang berpengaruh
terhadap kelelahan.
6.3.3. Hubungan antara Aktivitas Fisik dengan Kelelahan
Menurut Almatsier (2004) mengatakan bahwa aktivitas fisik dapat
didefinisikan sebagai gerakan fisik yang dilakukan oleh otot tubuh dan
sistem penunjangnya. Menurut Depkes RI (2006) aktivitas fisik adalah
pergerakkan anggota tubuh yang menyebabkan pengeluaran tenaga secara
sederhana minimal 30 menit dalam sehari selama 5 hari dalam seminggu
yang sangat penting bagi pemeliharaan fisik, mental, dan kualitas hidup
sehat. Aktivitas fisik juga dapat terjadi dalam melakukan aktivitas seperti
pekerjaan rumah, berkebun, melakukan hobi, rekreasi dan olahraga
(Allender & Spradley, 2001 dalam Achmanagara, 2012). Aktivitas fisik
yang berlebihan merupakan salah satu faktor terjadinya kelelahan (Pearl
Medic, 2011). Dalam hal ini jenis aktivitas fisik yang dilakukan oleh ibu
menyusui adalah aktivitas rumah tangga yaitu seperti mengepel lantai dan
membersihkan rumah dengan banyak menggunakan tangan, menjemur
pakaian, mengelap kaca jendela, memindahkan barang ringan,
membereskan peralatan, membuang sampah, dan berbagai pekerjaan
rumah tangga sehari-hari.
123
Hasil dari analisis univariat bahwa rata-rata aktivitas fisik ibu
menyusui ≤ enam bulan adalah 19015.15 METs, dengan nilai minimum
1465.50 METs, dan maksimum 96390 METs. Hal ini menunjukkan
bahwa rata-rata aktivitas fisik ibu menyususi dibawah enam bulan
termasuk aktivitas fisik berat. Hal ini terjadi dimungkinkan karena selain
ibu bertugas mengerjakan seluruh tugas rumah tangga ibu juga dibebani
rutinitas rutinitas menyusui. Oleh karena itu, disaranakan setelah ibu
menyelesaikan pekerjaan baik itu rumah tangga maupun menyusui, ibu
dianjurkan untuk beristirahat minimal selama 15 menit untuk
mempertahankan efisiensi dan performa tubuh. Hal ini sesuai dengan
pendapat Manuaba (1990) dalam Virgy (2011) yang mengatakan bahwa
setiap fungsi tubuh memerlukan keseimbangan yang ritmis antara asupan
energy dan pengganti energy (kerja-istirahat), maka diperlukan adanya
waktu istirahat pendek (15 menit setelah 1,5-2 jam kerja) untuk
mempertahankan efisiensi dan performa kerja. Hasil analisis hubungan
antara aktivitas fisik dengan kelelahan pada ibu menyusui dibawah enam
bulan di Kelurahan Pisangan Ciputat Timur 2013 dengan nilai signifikan
95% diperoleh bahwa nilai Mean Rank untuk ibu menyusui yang
mengalami kelelahan sebesar 17.77 dengan nilai P-value 0,168 yang
lebih besar dari 0,05. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada
hubungan antara aktivitas fisik dengan terjadinya kelelahan. Hasil ini
sejalan dengan penelitian Mamuaja (2011) menunjukkan bahwa tidak
124
terdapat hubungan yang nyata (p>0,05) antara tingkat kelelahan dengan
tingkat aktivitas fisik hari kerja dan libur. Hal ini disamakan dengan
aktivitas fisik hari kerja dan libur karena aktivitas fisik rumah tangga
dilakukan tanpa memandang status hari yang ada.
Ketidaksesuaian tersebut dapat dimungkinkan adanya faktor lain
yang tidak diteliti dalam penelitian ini yang berpengaruh terhadap
kelelahan.
6.4. Analisis Faktor Karakteristik Pekerjaan (Risiko Ergonomi Postur
Menyusui, Lama Menyusui dan Lingkungan Menyusui) pada Ibu Menyusui
≤ 6 Bulan di Kelurahan Pisangan Ciputat Timur 2013
6.4.1. Hubungan antara Risiko Ergonomi Postur Menyusui dengan
Kelelahan
Kegiatan menyusui merupakan kegiatan yang membutuhkan
kesabaran karena lamanya waktu yang dibutuhkan dan bersifat incidental
karena tidak bisa dijadwalkan. Ada berbagai macam posisi menyusui
yang baik dan perlu diketahui oleh para ibu. Hal ini penting karena
berkaitan dengan kenyamanan yang didapat baik oleh ibu maupun bayi.
Namun biasanya ibu lebih memprioritaskan kenyamanan bayinya tanpa
mempertimbangkan kenyamanan postur yang digunakan.
Menurut Pheasant (2003), postur kerja dipengaruhi oleh
hubungan antara dimensi tubuh dan stasiun kerjanya (workstation).
Misalnya, tempat kerja yang terlalu tinggi untuk pekerja yang memiliki
125
tinggi badan rendah atau tempat kerja yang terlalu rendah untuk pekerja
dengan tinggi badan lebih. Berdasarkan penjelasan Pheasant (2003) ini
dapat dikatakan bahwa postur duduk ibu saat menyusui dengan posisi
duduk juga dipengaruhi oleh posisi duduk ibu itu sendiri, dimana ibu
harus menyesuaikan posisi ibu dengan bayi yang disusuinya supaya posisi
bayi pas dan tepat untuk menyusu.
Sumber kelelahan ibu saat menyusui antara lain dapat berasal dari
postur yang digunakan ibu yang menuntut beberapa bagian tubuh untuk
menopang beban yaitu pada lengan tangan serta pembungkukan
punggung dan leher yang terjadi karena ibu lebih fokus memperhatikan
proses laktasi bayi tanpa mempertimbangkan risiko postur yang
dipergunakan oleh ibu yang mampu menyebabkan kejanggalan seperti
kontraksi otot yang mampu memicu terjadinya kelelahan otot setempat.
Hal ini sejalan dengan pendapatnya Waters dan Bhattacharya (1996)
yang dikutip oleh Tarwaka dkk, (2004) berpendapat bahwa kontraksi otot
baik statis maupun dinamis dapat meyebabkan kelelahan otot setempat.
Kelelahan tersebut terjadi pada waktu ketahanan (Endurance time) otot
terlampaui. Waktu ketahanan otot tergantung pada jumlah tenaga yang
dikembangkan oleh otot sebagai suatu prosentase tenaga maksimum yang
dapat dicapai oleh otot. Kemudian pada saat kebutuhan metabolisme
dinamis dan aktivitas melampaui kapasitas energi yang dihasilkan oleh
126
tenaga kerja, maka kontraksi otot akan terpengaruh sehingga kelelahan
seluruh badan terjadi.
Hasil dari analisis univariat bahwa rata-rata risiko ergonomi
postur menyusui adalah 6,84 dengan nilai minimum 6 dan nilai
maksimum 7. Ibu yang mengalami risiko ergonomi sedang 15,8% dan
ibu yang risiko ergonomi tinggi 84,2%. Hal ini menyatakan bahwa posii
menyusui yang digunakan oleh seluruh ibu berisiko.
Postur duduk ibu berada pada level risiko sedang disebabkan
karena posisi lengan, pergelangan tangan, leher, dan punggung ibu. Ibu
membengkokkan lengan dan pergelangan tangan ibu ke bawah untuk
menyangga bayi. Leher ibu menunduk dan bengkok karena selama
aktivitas menyusui berlangsung ibu untuk memperhatikan keluarnya ASI
dari payudara ibu agar bayi tidak tersedak. Sedangkan sikap punggung
ibu menyesuaikan dengan ketepatan posisi bayi untuk menyusu. Hal ini
jika dibiarkan akan berisiko terjadinya kelelahan lanjut yang mampu
mengakibatkan MSDs (Musculosceletal Disorders).
Hasil analisis hubungan antara risiko ergonomi postur menyusui
dengan kelelahan pada ibu menyusui dibawah enam bulan di Kelurahan
Pisangan Ciputat Timur 2013 dengan nilai signifikan 95% diperoleh
bahwa nilai Mean Rank untuk ibu menyusui yang mengalami kelelahan
sebesar 19,29 dengan nilai P-value sebesar 0,441 yang lebih besar dari
127
0,05 hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara
postur menyusui dengan terjadinya kelelahan.
Hasil uji statistik menunjukkan tidak adanya hubungan antara
postur menyusui dengan kelelahan. Akan tetapi berdasarkan penilaian
RULA kegiatan menyusui tersebut masuk level risiko sedang dengan
nilai mean 6,87 yang membutuhkan tindakan dalam waktu dekat.
Menurut Soeripto (1989), perencanaan dan produktivitas, menciptakan
keselamatan dan kesehatan kerja serta kelestarian lingkungan kerja, dan
juga memperbaiki kualitas produk dari suatu proses produksi. Oleh
karena itu, upaya untuk menanggulangi risiko ergonomik tersebut dapat
dilakukan dengan penyediaan peralatan kerja yang sesuai dengan
antropometri ibu menyusui dan dalam hal ini adalah seperti kursi
kkhusus untuk ibu menyusui. Dengan demikian risiko ergonomi dapat
diminimalisasi. Selain itu perlu juga memberikan pelatihan kepada ibu
menyusui maupun calon ibu menyusui (ibu hamil) tentang cara menyusui
yang benar, yaitu dengan memperagakan posisi menyusui yang benar,
pemilihan tempat duduk atau alat bantu yang tepat untuk menyusui.
sehingga akan mengurangi risiko ergonomi bagi ibu selama menyusui.
Pelatihan sebaiknya diberikan sedini mungkin supaya ketika ibu hamil
menjadi ibu menyusui sudah dapat melakukan teknik menyusui yang
benar dari awal kegiatan atau proses menyusui dilakukan. Pelatihan dapat
128
diberikan melalui kelas ibu hamil khususnya masuk dalam materi
pemeberian ASI eklusif/Inisiasi Menyusui Dini (IMD), karena dalam
kelas ini ibu hamil akan belajar bersama, diskusi dan tukar pengalaman
tentang kesehatan ibu dan anak secara menyeluruh dan sistematis serta
dapat dilaksanakan secara terjadwal dan berkesinambungan (Depkes RI,
2009).
6.4.2. Hubungan antara Lama Menyusui dengan Kelelahan
Menyusui merupakan kegiatan yang dilakukan selama berjam-jam
dan berkali-kali setiap harinya oleh ibu pasca melahirkan. Disebutkan
juga dalam buku An Easy Guide to Breastfeeding bahwa menyusui
dilakukan minimal 2 jam sekali, namun waktu menyusui ini tidak boleh
dijadwal secara ketat karena semakin sering bayi menyusu, maka akan
menstimulasi payudara ibu untuk memproduksi lebih banyak ASI.
Sehingga kegiatan menyusui merupakan kegiatan yang membutuhkan
waktu yang lama dan dilakukan berkali-kali dalam sehari baik malam
maupun siang. Hal ini mampu memicu terjadinya kelelahan karena
lamanya waktu yang dibutuhkan dan sering kalinya dilakukan tanpa
memandang waktu dengan posisi yang statis dan pembebanan pada
anggota badan sehingga beberapa bagian otot setempat yang digunakan
berisiko terjadinya kontraksi otot yang mampu memicu terjadiny
kelelahan.
129
Menurut Suma’mur (1981) bekerja merupakan proses anabolisme,
yaitu mengurangi atau menggunakan bagian-bagian tubuh yang telah
dibangun sebelumnya. Dalam keadaan demikian, sistem syaraf utama
yang berfungsi adalah komponen simpatis. Maka pada kondisi tersebut,
aktifitas tidak dapat dilakukan secara terus menerus, melainkan harus
diselingi dengan istirahat untuk memberikan kesempatan membangun
kembali tenaga yang telah digunakan. Meskipun menyusui merupakan
kegiatan yang sifatanya tidak dilakukan dalam sekali waktu namun
berjeda yang bisa digunakan untuk istirahat namun waktu istirahat
tersebut biasanya dimanfaatkan oleh ibu menyusui untuk melakukan
aktifitas rumah tangga seperti mengepel, menyapu, mencuci, menyetrika
dan lain sebagainya.
Lama kerja bagi seseorang menentukan efisiensi dan
produktifitasnya. Lamanya seseoarang bekerja sehari secara baik pada
umumnya 6-8 jam. Sisanya 16-18 jam dipergunakan untuk kehidupan
dalam keluarga dan masyarakat, istirahat, tidur dan lain-lain.
Memperpanjang waktu kerja lebih dari kemampuan tersebut biasanya
tidak disertai efisiensi yang tinggi, bahkan biasanya terlihat penurunan
produktifitas serta kecenderuangan untuk timbulnya kelelahan, penyakit
dan kecelakaan kerja (Suma’mur, 1996).
130
Di Indonesia telah ditetapkan lamanya waktu kerja sehari
maksimum 8 jam kerja (480 menit) dan sisanya untuk
istirahat/kehidupan dalam keluarga dan masyarakat. Manuaba (1990)
dalam Virgy (2011) menjelaskan bahwa jam kerja berlebihan, jam kerja
lembur diluar batas kemampuan akan mempercepat timbulnya kelelahan.
Hasil dari analisis univariat bahwa rata-rata status lama menyusui ibu
dibawah enam bulan adalah 183.92 menit dengan nilai minimum 25
menit dan nilai maksimum 900 menit. Hal ini menunnjukkan bahwa rata-
rata jam kerja ibu menyusui dibawah enam bulan termasuk kategori
aman.
Hasil analisis hubungan antara jam kerja dengan kelelahan pada
ibu menyusui dibawah enam bulan di Kelurahan Pisangan Ciputat Timur
2013 dengan nilai signifikan 95% diperoleh bahwa nilai Mean Rank
untuk ibu menyusui yang mengalami kelelahan sebesar 19.23 dengan
nilai P-value 0,063 yang lebih besar dari 0,05, hal tersebut dapat
disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara jam kerja dengan
terjadinya kelelahan.
Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Safitri
(2008) dan Andiningsari (2009) yang menyatakan tidak ada hubungan
antara jam kerja dengan kelelaha kerja. Hal ini dimungkinkan karena
rata-rata lama kegiatan menyusui dalam sehari masuk kategori aman.
Sehingga sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah dianjurkan.
131
6.4.3. Hubungan antara Kebisingan dengan Kelelahan
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan tempat ibu
menyusui dengan posisi duduk, kesemuanya memiliki tingkat kebisingan
lebih dari 55 dB yaitu nilai mean kebisingan 66.837 dB dengan nilai
minimum 60,6 dB dan maksimum 81.4 dB. Hal ini berarti bahwa
lingkungan tempat ibu menyusui berada di atas nilai ambang batas yang
diperbolehkan untuk wilayah pemukiman menurut Keputusan Menteri
Negara Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat
Kebisingan, tingkat kebisingan yang diperbolehkan untuk kawasan
perumahan dan pemukiman yaitu tidak lebih dari 55 dB. Menurut
Rusdjijati dan Widodo (2008), jika nilai kebisingan sudah melebihi Nilai
Ambang Batas yang ditetapkan, maka dapat mengakibatkan
ketidaknyamanan bagi manusia yang menerima kebisingan tersebut.
Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kebisingan di suatu
tempat. Menurut Mashuri (2007) dalam Anggraini et. al (2012) , faktor-
faktor tersebut terdiri dari jarak, serapan udara, angin, dan permukaan
bumi.
Tidak ada sumber kebisingan yang berarti di lingkungan tempat
tinggal responden. Rata-rata sumber kebisingan berasal dari keramaian
masyarakat (seperti suara anak-anak, orang-orang yang sedang
mengobrol, dan sebagainya). Namun, bagi tempat tinggal ibu yang
berada dekat dengan jalan raya, maka sumber kebisingannya selain dari
132
keramaian masyarakat juga dapat berasal dari lalu lintas kendaraan
bermotor.
Pada saat dilakukan pengumpulan data, adakalanya cuaca panas
dan adakalanya mendung. Hal ini mempengaruhi kondisi angin dan
udara. Udara yang bersuhu rendah akan lebih menyerap suara daripada
udara bersuhu tinggi. Selain itu juga, besarnya frekuensi bunyi yang
diterima juga dipengaruhi oleh arah angin. Arah angin yang menuju
pendengar akan mengakibatkan suara terdengar lebih keras, begitu juga
sebaliknya. (Mashuri, 2007 dalam Anggraini, 2012).
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara
kebisingan dengan kelelahan. Kemungkinan dengan tidak adanya
hubungan tersebut disebabkan oleh lamanya ibu tinggal di lingkungan
tersebut sehingga kemungkinan ibu sudah terbiasa dan lebih
berpengalaman untuk mengatur besarnya tenaga yang dikeluarkan oleh
karena seringnya melakukan pekerjaan tersebut, sehingga kelelahan tidak
terjadi pada saat menyusui berlangsung.
6.4.4. Hubungan antara Pencahayaan dengan Kelelahan
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai mean pencahayaan
adalah 130.050 lux dengan nilai minimum 12.0 lux dan nilai maksimum
803.0 lux. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 1077/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Penyehatan Udara
dalam Ruang Rumah, pencahayaan yang disyaratkan minimal 60 Lux. .
133
Nilai pencahayaan yang terukur di tempat ibu menyusui sesuai dengan
Nilai Ambang Batas yang ditetapkan.
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara
pencahayaan dengan kelelahan. Hal ini kemungkinan disebabkan karena
aktivitas menyusui tidak dipengaruhi oleh tingkat pencahayaan karena
aktivitas menyusui tidak didominasi oleh penggunaan indera penglihatan
sebagaimana pada pekerja yang berhubungan dengan komputer selama
waktu kerjanya.
6.4.5. Hubungan antara Suhu dengan Kelelahan
Pada penelitian ini, nilai mean suhu adalah 32.566 o
C dengan
nilai minimum 31oC dan maksimum 37
oC. Menurut Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1077/MENKES/PER/V/2011
tentang Pedoman Penyehatan Udara dalam Ruang Rumah, kadar yang
diisyaratkan untuk suhu di dalam rumah adalah antara 18-30oC. Nilai
suhu yang terukur di tempat ibu menyusui melebihi Nilai Ambang Batas
yang ditetapkan. Pada penelitian ini, tingginya suhu yang terukur
kemungkinan disebabkan karena faktor cuaca.
Menurut Suma’mur (1992) pada suhu udara yang panas dan
lembab, makin tinggi kecepatan aliran udara malah akan makin
membebani tenaga kerja. Pada tempat kerja dengan suhu udara yang
panas maka akan menyebabkan proses pemerasan kringat. Beberapa hal
134
buruk berkaitan dengan kondisi demikian dapat dialami oleh tenaga kerja,
salah satunya kelelahan kerja. Pekerja yang mengalami kondisi demikian,
sulit untuk mampu bereproduksi tinggi. Akibat kelelahan kerja tersebut,
para pekerja menjadi kurang bergairah kerja, daya tanggap dan rasa
tanggung jawab menjadi rendah, sehingga seringkali kurang
memperhatikan kualitas produk kerjanya.
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan
antara suhu dengan kelelahan. Kemungkinan dengan tidak adanya
hubungan tersebut disebabkan oleh lamanya ibu tinggal di lingkungan
tersebut sehingga kemungkinan ibu sudah terbiasa dan lebih
berpengalaman untuk mengatur besarnya tenaga yang dikeluarkan oleh
karena seringnya melakukan pekerjaan tersebut, sehingga kelelahan tidak
terjadi pada saat menyusui berlangsung.
135
BAB VII
SIMPULAN DAN SARAN
7.1. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada ibu menyusui ≤ 6
bulan di Kelurahan Ciputat Timur 2013 diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Gambaran kelelahan postur menyusui pada ibu menyusui ≤ 6 bulan di
Kelurahan Pisangan Ciputat Timur 2013 adalah rata-rata 92.1% ibu menyusui
mengalami kelelahan.
2. Gambaran rata-rata factor risiko ergonomic postur menyusui (risiko sedang =
6,87), usia (27 tahun), status gizi (25.3013 = kelebihan berat badan tingkat
ringan), lama menyusui (183.92 menit = kategori aman), aktivitas fisik
(19015.15 METs = aktivitas fisik berat), pencahayaan (130.050 lux= sesuai
peratuaran), suhu (32.566 oC= melebihi nilai ambang batas yang ditetapkan),
kebisingan (66.837 dB = di atas nilai ambang batas yang diperbolehkan) pada
ibu menyusui ≤ 6 bulan di Kelurahan Pisangan Ciputat Timur 2013.
3. Tidak ada hubungan antara karakteristik individu (usia, status gizi, aktivitas
fisik dengan kelelahan pada ibu menyusui ≤ 6 bulan di Kelurahan Pisangan
Ciputat Timur 2013.
136
4. Tidak ada hubungan antara karakteristik pekerjaan (risiko ergonomic postur
menyusui, lama menyusui dan lingkungan menyusui) dengan kelelahan pada
ibu menyusui ≤ 6 bulandi Kelurahan Pisangan Ciputat Timur 2013.
7.2. Saran
Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah:
1. Bagi Ibu Menyusui
a. Saran yang dapat diberikan kepada ibu menyusui berdasarkan hasil
penelitian ini adalah memberikan pelatihan kepada ibu menyusui maupun
calon ibu menyusui (ibu hamil) tentang cara menyusui yang benar, yaitu
dengan memperagakan posisi menyusui yang benar, pemilihan tempat
duduk atau alat bantu yang tepat untuk menyusui. Sehingga akan
mengurangi risiko ergonomi bagi ibu selama menyusui. Pelatihan
sebaiknya diberikan sedinimungkin supaya ketika ibu hamil menjadi ibu
menyusui sudah dapat melakukan teknik menyusui yang benar dari awal
kegiatan atau proses menyusui dilakukan. Pelatihan dapat diberikan
melalui kelas ibu hamil.
b. Disarankan setelah ibu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga ibu
beristirahat minimal selama 15 menit untuk mempertahankan efisiensi
dan performa tubuh.
137
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
a. Diharapkan peneliti selanjutnya dalam mengukur kelelahan menggunakan
Reaction Timer Test yang sesungguhnya, bukan dari layar komputer.
b. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian khusus
tentang desain kursi untuk ibu menyusui dengan mempertimbangkan
faktor ergonomi.
c. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melihat lebih jauh lagi hubungan
faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kelelahan saat menyusui
sehingga dapat diketahui dengan jelas mekanisme terjadinya kelelahan
ibu saat menyusui dan faktor apa saja yang mempengaruhi atau yang
paling berpengaruh terhadap terjadinya kelelahan ibu saat menyusui.
DAFTAR PUSTAKA
Almatsier, Sunita. 2004. Prinsip Dasar Ilmu Gizi. Jakarta: Gramedia. 132-150
An Easy Guide to Breastfeeding. 2006. U.S. Departement of Health and Human
Services Office on Woman’s Health
Andiningsari, Pratiwi. 2009. Hubungan Faktor Internal Dan Ekternal Terhadap
Kelelahan Pada Pengemudi Travel X Trans Jakarta Trayek Jakarta-Bandung.
Skripsi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia
Anies. 2002. Bebagai Penyakit Akibat Lingkungan Kerja Dan Upaya
Penanggulangannya, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
Auditya. 2011. Perlekatan Menyusu dan Berbagai Posisi Menyusui. Availabel:
http://informasitips.com diakses pada tanggal 27 Juni 2012
Battevi, Natale, Hedge. Handbook of Human Factor and Ergonomics. Availabel:
http://www.ergonomics.co.uk/Rula/Ergo/index.html diakses pada tanggal 7
September 2012
Budiono, dkk. 2003. Kelelahan (Fatigue) Pada Tenaga Kerja. Bunga Rampai
Hiperkes Dan Keselamatan Kerja. Edisi Ke-2. Semarang; Universitas
Diponegoro
Bustan. 2000. Epidemiologi Penyakit Tidak Menula. Jakarta : PT. Rineka Cipta
Depkes RI. 2006. Pusat Kesehatan Kerja. Promosi Kesehatan. Availabel:
http://www.depkes.go.id. diakses pada tanggal 22 Januari 2013
Depkes RI. 2009. Pegangan Fasilitator Kelas Ibu Hamil. Availabel:
http://www.depkes.go.id. diakses pada tanggal 25 Juli 2013
Dowell, Chad H & Tapp. Loren C. 2007. Evaluation of Heat Stress at a Glass Bottle
Manufacturer. Departement of Health and Human Service National Institude
for Occupational Safety and Health (NIOSH). Cincinati.ohio. [cited 2009 June
27th]. Availade : http:www.ctc.gov/niosh/hhe/reports/pdfs/2003-
0311.3052.Pdf.
Farrer, Helen. 1999. Perawatan Maternitas. Jakarta: EGC
Fredregill, Suzanne dan Ray Fredregill. 2010. The Everything Breastfeeding Book.
Second Edition. U.S.A: F+W Media Inc.
Gunawan, Agung Fadly. 2012. Nursing Care And Health Tips. Availabel:
http://agungfadlygunawan.blogspot.com/2012_08_01_archive.html diakses
pada tanggal 25 November 2012
http://www.bppsdmk.depkes.go.id/ diakses 14 januari 2013 pukul 11.56
J Hum lact University of Kansas School of Nursing, Kansas City 66160-7502,
Amerika Serikat 1998 Mother breastfeeding primiparae fatigue during the first
nine weeks postpartum.
Kasanah, Erni. 2011. Tingkat Pengetahuan Diet TKTP Dan Asupan Energy, Protein
Pada Pasien Rawat Jalan Dib Alai Pengobatan Penyakit Paru-Paru
Yogyakarta. Karya Ilmiah. Kementrian Kesehatan Republic Indonesia
Politeknik Kesehatan Yogyakarta.
Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) No.829/Menkes/SK/VII/1999
Tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
450/MENKES/SK/IV/2004 Tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara
Eksklusif pada Bayi di Indonesia
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996 Tentang Baku
Mutu Kebisingan Untuk Perumahan Dan Pemukiman
Lisa, Schlein. 2008. Study Finds Early Breastfeeding Can Save Babies’ Lives.
Availabel: http://smartparent.wordpress.com/category/asi/page/9/. Diakses 28,
juni 2012
Manuaba. A. 1998. Bunga Rampai Ergonomi Vol 11. Program Studi Ergonomi
Fisiologi Kerja Universitas Udayana,
Marfu’ah, Umi. 2007. Ergonomi Cegah Terjadinya Penyakit Akibat Kerja. Majalah
KATIGA, Bisnis, K3
Mauludi, Noval. 2010. Factor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kelelahan Pada
Pekerja Diproses Produksi Kantong Semen PBD (Paper Bag Devision)
PT.Indocement Tunggal Prakasa Tbk Citeureup Bogor. UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta
Miligan, RA., Flenniken,PM.,& Pugh,LC. 1996. Positioning intervention to minimize
fatigue in breastfeeding women. Applied Nursing Research, Vol.9 no.2
(May).1996 : pp.67-70
Notoatmodjo, Soekidjo. 1997. Prinsip-Prinsip Dasar Kesehatan Masyarakat. Jakarta:
PT. Rineka Cipta
Notoatmodjo, Soekidjo. 2002. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: PT. Rineka
Cipta
Nugraha, Ika. 2010. Hubungan Derajat Berat Merokok Berdasarkan Indeks
Brinkman Dengan Derajat Berat PPOK. Akper Patria Husada Surakarta.
Available:
http://stikespku.ac.id/ejournal/index.php/profesi/article/download/15/13
Nurhidayati, Puti. 2009. Hubungan Antara Penerapan Shift Kerja Dengan Kelelahan
Kerja Pada Pekerja Dibagian Produksi PT.TIFICO, TBK. UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta
Nurmianto, Eko. 2003. Ergonomi Konsep Dasar Dan Aplikasinya. Surabaya: Guna
Widya
Oentoro, S. 2004. Kampanye Atasi Kelelahan Mental Dan Fisik. Jakarta: UI Press
Parubak,Byzantine Wulandari, 2011, Hubungan Antara Kurangnya Aktivitas Fisik
Tubuh Terhadap Resiko Osteoporosis Pada Waktu Usia 45-65 Tahun
Dirumah Sakit Undata Palu.Universitas Tadulako
Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif
Pheasant, Stephen. 1991. Ergonomics, Work and health. Gaithersburg. Maryland
Preal Madic. 2011. Waspada Kelelahan Akibat Bekerja. Availabel:
http://www.mutiaramedicalservice.com/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=71. diakses pada tanggal 22 Januari 2013
Roesli, Utami. 2000. Mengenal ASI Eksklusif . Jakarta: PT Niaga Swadaya
Roesli, Utami. 2009. Panduan Praktis Menyusui. Jakarta: Pustaka Bunda. Cet. I
Rohman, Abdul. 2012. Program Laktasi Intervensi Dalam Upaya Meningkatkan
Durasi Dan Mengurangi Kelelahan Saat Menyusui. Malang: Fakultas
Kedokteran Universitas Brawijaya
Safitri, Dian Sustana. 2008. Hubungan Antara Pola Kerja Dengan Kelelahn Kerja
Pada Karyawan Perusahaan Migas X Kalimantan Timur. Skripsi Fakultas
Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia
Saswita. Dewi. 2006. Analisis Tingkat Kelelahan Pada Pekerja Shift Di PT “X”
Citereup- Bogor. Skripsi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas
Indonesia
Sedarmayanti. 2009. Tata Kerja Dan Produktiitas Kerja. Bandung: Mandar Maju
Setyawati, Ely. 2001. Identifikasi Factor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Tingkat
Kelelahan Kerja Pada Tenaga Kerja Wanita Bagian Produksi Jahit Garmen
PT.Billion Jakarta Pusat. Skripsi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas
Indonesia
Silastuti, Ambar. 2006. Hubungan Antara Kelelahan Dengan Produktivitas Tenaga
Kerja Di Bagian Penjahitan Pt Bengawan Solo Garment Indonesia.
Uneversitas Negri Semarang.
Sisinta, Tiaraima. 2005. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kelelahan Pada
Pekerja Di Departemen Weaving PT.ISTEM Tangerang. Skripsi Fakultas
Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia
Soeripto. 1989. Ergonomi Dan Produktifitas Kerja. Majalah Hiperkes Dan
Keselamatan Kerja. Vol XXII No. 1
Soetjiningsih. 1997. Seri Gizi Klinik, ASI:Petunjuk Untuk Tenaga Kesehatan. Jakarta:
Penerbit Buku Kedokteran EGC. Cetakan I (Ed)
Suma’mur PK. 1999. Ergonomi Untuk Produktivitas Kerja. Jakarta: CV Haji
Masagung
Suma’mur. 1981, 1996. Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan. Jakarta:
PT. Toko Gunung Agung
Suma’mur. 1989. Ergonomi untuk Produktivitas Kerja. Jakarta: Haji Mas Agung
Suma’mur. 1995. Hygiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja. Jakarta: PT. Gunung
Agung
Suryani. 2012. Manurung, Program Laktasi Intervensi Dalam Upaya Meningkatkan
Durasi Dan Mengurangi Kelelahan Saat Menyusui. Diambil dari
www.fik.ui.ac.id/pkko/files/tugas%20sim%20ppko.Doc. Diakses 28juni 2012
Tarwaka, Solichul, Bakri, Lilik Sudiajeng. 2004. Ergonomi Untuk Kesehatan Kerja
Dan Produktivitas. Surakarta: UNIBA Press.
Umyati. 2010. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kelelahan Kerja Pada
Pekerja Penjahit Sector Usaha Informal Di Wilayah Ketapang Cipondoh
Tangerag Tahun 2009. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Victorian, 1985. Manual Handling. Melbourne. Vic 3000
Virgi, Sulistya. 2011, Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kelelahan Kerja
Pada Karyawan Di Instalasi Gizi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar
Rebo Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Widodo, Ariani Dewi. 2011. Posisi Menyusui yang Nyaman Bagi Ibu dan Buah Hati.
Available: http://www.tanyadok.com/anak/posisi-menyusui-yang-nyaman-
bagi-ibu-dan-buah-hati. Diakses pada tanggal 16 Januari 2013 pukul 11.40
World Health Organization. 1991.Indicators for Assessing Breastfeeding Practices
Devision of Child Healt and Development, Geneva.
Lampiran 1: Pernyataan Persetujuan Menjadi Responden Penelitian
PENYATAAN PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN
Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Saya mahasiswa S1 Peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Program Studi
Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri
(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta sedang melakukan penelitian tentang “Faktor-Faktor Yang
Berhubungan Dengan Terjadinya Kelelahan Pada Ibu Menyusui ≤ 6 Bulan Di Kelurahan
Pisangan Ciputat Timur Tahun 2013”. Penelitian ini saya lakukan sebagai syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Sehubungan dengan hal tersebut, saya meminta kesediaan Ibu untuk menjadi responden
dalam penelitian ini dimana akan diberikan kuesioner dan dilakukan observasi serta wawancara
mendalam terkait dengan aktivitas menyusui ibu. Semua informasi yang Ibu berikan dan peneliti
amati akan terjamin kerahasiaannya. Setelah Ibu membaca maksud dan kegiatan penelitian ini,
maka saya meminta Ibu untuk mengisi nama dan tanda tangan di bawah ini.
“Saya yang bertanda tangan di bawah ini bersedia menjadi responden pada penelitian ini dan
akan memberikan informasi yang diminta dengan sebenar-benarnya”.
Nama: ____________________________________________________________________
Tanda Tangan:
____________________________________________________________________
Atas kesediaan dan partisipasi Ibu, saya ucapkan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Warohmatullah Wabarokatuh
Ciputat, ______________2013
Hormat Saya,
Liazul Kholifah
Posyandu
No. Responden
Tanggal Pengumpulan Data: dd/mm/yyyy
Lampiran 2: Instrumen Penelitian
KUESIONER PENELITIAN
Pertanyaan 1
A. Informasi Umum Responden
A.1 Posisi yang digunakan ibu saat menyusui:
1) Duduk (Lanjut) 2) Berbaring (Selesai)
A.2 Apakah saat ini Ibu bekerja?
1) Iya (Selesai) 2) Tidak (Lanjut)
A.3 Nama Ibu : _______________________________
A.4 Tanggal Lahir Ibu : __ __ / __ __ / __ __ __ __
A.5 Tanggal Lahir Bayi : __ __ / __ __ / __ __ __ __
A.6 Bayi adalah anak ke- : __
A.7 Alamat : _________________________________
_________________________________
A.8 No. Telp./Hp : ________________________
B. Informasi Aktivitas Menyusui
B.1 Berapa kali Ibu menyusui dalam sehari: __ __ kali 99. Lupa/Tidak tahu
B.2 Jika saat ini, sudah berapa kali Ibu menyusui? __ __ kali 99. Lupa/Tidak tahu
B.3 Berapa lama Ibu menyusui dalam sehari per menyusui: __ __ menit 99. Lupa/Tidak tahu
C. Apa saja aktivitas Ibu sebelum menyusui saat ini? (Bacakan pilihan jawaban dan jawaban boleh lebih dari
satu)
No. Aktivitas Ya Tidak
C.1 Mencuci dengan tangan 1 2
C.2 Mencuci dengan mesin cuci 1 2
C.3 Menjemur pakaian 1 2
C.4 Memasak 1 2
C.5 Mengepel lantai 1 2
C.6 Menyapu lantai 1 2
C.7 Membersihkan halaman 1 2
C.8 Membereskan peralatan 1 2
C.9 Membersihkan rumah dengan banyak menggunakan tangan 1 2
C.10 Membuang sampah 1 2
C.11 Berkebun 1 2
C.12 Mengelap kaca jendela 1 2
C.13 Nonton TV 1 2
C.14 Mengantarkan anak ke sekolah dengan berjalan kaki 1 2
C.15 Mengantarkan anak ke sekolah dengan bersepeda 1 2
A1 ( )
A2 ( )
A4 ( )
A5 ( )
A6 ( )
B1 ( )
B2 ( )
B3 ( )
C1 ( )
C2 ( )
C3 ( )
C4 ( )
C5 ( )
C6 ( )
C7 ( )
C8 ( )
C9 ( )
C10 ( )
C11 ( )
C1l2( )
C13 ( )
C14 ( )
Posyandu
No. Responden
Tanggal Pengumpulan Data: dd/mm/yyyy
C.16 Bersosialisasi dengan tetangga sekitar 1 2
C.17 Mengikuti kegiatan di masyarakat 1 2
C.18 Lainnya, sebutkan ___________________ 1 2
D. Bagian ini tentang aktivitas fisik yang ibu lakukan dalam 7 hari terkhir di dalam dan di sekitar rumah,
seperti pekerjaan rumah tangga, pekerjaan berkebun di halaman, pekerjaan pemeliharaan umum, dan
merawat keluarga ibu.
D.1 Pikirkan hanya aktivitas fisik yang ibu lakukan selama setidaknya 10 menit pada suatu waktu.
Selama 7 hari terakhir, berapa hari ibu melakukan kegiatan fisik yang kuat seperti angkat
berat, memotong kayu, menyekop tanah/pasir, atau menggali di taman atau halaman?
_____ Hari per minggu
99. Tidak ada aktivitas yang berat di kebun atau halaman pertanyaan D.3.3
D.2 Berapa banyak waktu yang biasanya ibu habiskan pada salah satu dari hari-hari melakukan
kegiatan fisik yang kuat di kebun atau halaman?
_____ Jam per hari
_____ Menit per hari
D.3 Sekali lagi, pikirkan hanya aktivitas fisik yang ibu lakukan selama setidaknya 10 menit pada
suatu waktu. Selama 7 hari terakhir, berapa hari ibu melakukan aktivitas sedang seperti
membawa beban ringan, menyapu, mencuci jendela, dan menyapu di taman atau halaman?
_____ Hari per minggu
99. Tidak ada aktivitas sedang di kebun atau halaman pertanyaan D.3.5
D.4 Berapa banyak waktu yang biasanya ibu habiskan pada salah satu dari hari-hari melakukan
aktivitas fisik sedang di kebun atau halaman?
_____ Jam per hari
_____ Menit per hari
D.5 Sekali lagi, pikirkan hanya aktivitas fisik yang ibu lakukan selama setidaknya 10 menit pada
suatu waktu. Selama 7 hari terakhir, berapa hari ibu melakukan aktivitas sedang seperti
membawa beban ringan, mencuci jendela, menyikat lantai dan menyapu di dalam rumah ibu?
_____ Hari per minggu
99. Tidak ada aktivitas sedang di dalam rumah pertanyaan E1
D.6 Berapa banyak waktu yang Anda biasanya menghabiskan pada salah satu dari hari-hari
melakukan aktivitas fisik sedang dalam rumah ibu?
_____ Jam per hari
_____ Menit per hari
E. Status Merokok
E.1 Apakah Ibu pernah merokok?
1) Ya 2) Tidak, pertanyaan F1
C15 ( )
C16 ( )
C17 ( )
C18( )
D.1 ( )
D.2 ( )
D.3 ( )
D.4 ( )
D.5 ( )
D.6 ( )
E1 ( )
Posyandu
No. Responden
Tanggal Pengumpulan Data: dd/mm/yyyy
E.2 Jika iya, kapan terakhir kali Ibu merokok?
1) Hari ini 4) 1 tahun yang lalu
2) 1 minggu yang lalu 5) Lupa/Tidak tahu
3) 1 bulan yang lalu
E.3 Berapa batang rokok yang Ibu hisap setiap harinya? __ __ batang/hari 99. Lupa/Tidak tahu
E.4 Sejak umur berapa Ibu mulai merokok? __ __ tahun
F. Kelelahan
F.1 Pelemahan Kegiatan
No. Pertanyaan TP KK S SS
F.1 Apakah Ibu merasa berat di bagian kepala setelah
menyusui? 1 2 3 4
F.2 Apakah Ibu merasa lelah pada seluruh badan setelah
menyusui? 1 2 3 4
F.3 Apakah kaki Ibu merasa berat setelah menyusui? 1 2 3 4
F.4 Apakah Ibu menguap setelah menyusui? 1 2 3 4
F.5 Apakah pikiran Ibu terasa kacau setelah menyusui? 1 2 3 4
F.6 Apakah Ibu menjadi mengantuk setelah menyusui? 1 2 3 4
F.7
Apakah Ibu merasa ada beban pada mata (sakit di sekitar
mata, rasa berat pada kelopak mata, mata berair, penglihatan
kabur) setelah menyusui?
1 2 3 4
F.8 Apakah Ibu merasa canggung atau kaku dalam gerakan
setelah menyusui? 1 2 3 4
F.9 Apakah Ibu merasa sempoyongan/berdirinya tidak stabil
setelah menyusui? 1 2 3 4
F.10 Apakah Ibu ada perasaan ingin berbaring setelah menyusui? 1 2 3 4
F.2 Pelemahan Motivasi (Kesulitan Berkonsentrasi)
No. Pertanyaan TP KK S SS
F.1 Apakah Ibu merasa susah berpikir setelah menyusui? 1 2 3 4
F.2 Apakah Ibu merasa lelah berbicara setelah menyusui? 1 2 3 4
F.3 Apakah Ibu menjadi gugup setelah menyusui? 1 2 3 4
F.4 Apakah Ibu tidak bisa berkonsentrasi setelah menyusui? 1 2 3 4
F.5 Apakah Ibu tidak bisa memusatkan perhatian terhadap
sesuatu setelah menyusui? 1 2 3 4
F.6 Apakah Ibu mempunyai kecenderungan untuk lupa setelah
menyusui? 1 2 3 4
F.7 Apakah Ibu merasa kurang percaya diri setelah menyusui? 1 2 3 4
E2 ( )
E3 ( )
E4 ( )
F1 ( )
F2 ( )
F3 ( )
F4 ( )
F5 ( )
F6 ( )
F7 ( )
F8 ( )
F9 ( )
F10 ( )
F1 ( )
F2 ( )
F3 ( )
F4 ( )
F5 ( )
F6 ( )
Posyandu
No. Responden
Tanggal Pengumpulan Data: dd/mm/yyyy
F.8 Apakah Ibu merasa cenderung untuk membuat kesalahan
setelah menyusui? 1 2 3 4
F.9 Apakah Ibu merasa tidak bisa mengontrol sikap setelah
menyusui? 1 2 3 4
F.10 Apakah Ibu merasa tidak berenergi setelah menyusui? 1 2 3 4
F.3 Kelelahan Fisik
No. Pertanyaan TP KK S SS
F.1 Apakah Ibu merasa sakit kepala setelah menyusui? 1 2 3 4
F.2 Apakah Ibu merasa kaku di bagian bahu setelah menyusui? 1 2 3 4
F.3 Apakah Ibu merasa nyeri di punggung setelah menyusui? 1 2 3 4
F.4 Apakah nafas Ibu terasa tertekan setelah menyusui? 1 2 3 4
F.5 Apakah Ibu merasa sangat haus setelah menyusui? 1 2 3 4
F.6 Apakah suara Ibu terasa serak setelah menyusui? 1 2 3 4
F.7 Apakah Ibu merasa pening setelah menyusui? 1 2 3 4
F.8 Apakah kelopak mata Ibu terasa kaku setelah menyusui? 1 2 3 4
F.9 Apakah anggota badan Ibu terasa bergetar setelah
menyusui? 1 2 3 4
F.10 Apakah Ibu merasa kurang sehat setelah menyusui? 1 2 3 4
F7 ( )
F8 ( )
F9 ( )
F10 ( )
F1 ( )
F2 ( )
F3 ( )
F4 ( )
F5 ( )
F6 ( )
F7 ( )
F8 ( )
F9 ( )
F10 ( )
LEMBAR OBSERVASI
1. Lakukan “Reaction Timer Test” dan hasilnya masukkan ke dalam tabel berikut:
Rangsangan Waktu
Selisih Waktu Pengumpul Data Responden
1
2
3
4
5
Rata-rata
Posyandu
No. Responden
Tanggal Pengumpulan Data: dd/mm/yyyy
HASIL PENGUKURAN LANGSUNG
Faktor yang Diukur Hasil
Pengukuran
Tinggi Badan Ibu (cm)
Berat Badan Ibu (kg)
Indeks Massa Tubuh (IMT) Ibu
Berat Badan Bayi (kg)
Kebisingan (dB)
Suhu (oC)
Pencahayaan (Lux)
ANALISIS SETELAH PENGUMPULAN DATA
1. Skor Kelelahan:
a. Subjektif: __ __ __
b. Objektif: __ __ __
2. Berdasarkan skor kelelahan tersebut, maka tingkat kelelahan Ibu setelah menyusui adalah:
a. Subjektif:
1) Ringan
2) Sedang
3) Berat
b. Objektif:
1) Ringan
2) Sedang
3) Berat
3. Skor RULA: __ __
4. Dari skor RULA tersebut, maka level risiko Ibu saat menyusui dengan posisi duduk adalah:
1) Minimum: Skor 1-2
2) Kecil: Skor 3-4
3) Sedang: Skor 5-6
4) Tinggi: Skor 7
Lampiran 3: Contoh Analisis RULA
Langkah-langkah penilaian postur duduk ibu saat menyusui dengan metode RULA:
1. Diambil gambar postur duduk ibu saat menyusui melalui video.
2. Video yang telah direkam, kemudian dijadikan gambar-gambar sesuai dengan postur yang
diinginkan untuk dianalisis.
3. Ditentukan sudut-sudut bagian tubuh yang terbentuk dari postur duduk ibu saat menyusui
tersebut.
4. Ditentukan skor masing-masing bagian tubuh berdasarkan sudut yang dibentuk dan
ketentuan skor pada masing-masing bagian tubuh.
5. Skor tubuh grup A ditambahkan dengan skor aktivitas dan beban kemudian hasil
penjumlahannya dimasukkan ke dalam tabel C. Begitu juga dengan skor tubuh grup B
ditambahkan dengan skor aktivitas dan beban kemudian hasil penjumlahannya dimasukkan
ke dalam tabel C.
6. Diperoleh skor akhir RULA.
Contoh pada gambar di atas:
1. Skor Tubuh Grup A
a. Postur Lengan Atas
Sudut yang dibentuk adalah sebesar 35 derajat, sehingga skor untuk postur lengan atas
adalah 2.
b. Postur Lengan Bawah
Sudut yang dibentuk adalah sebesar 105 derajat, sehingga skor untuk postur lengan
bawah adalah 2.
c. Postur Pergelangan Tangan
Sudut yang dibentuk adalah sebesar 30 derajat dan menjauhi sisi tengah sehingga skor
untuk postur pergelangan tangan adalah 2 + 1 = 3
d. Putaran Pergelangan Tangan
Putaran pergelangan tangan ibu pada gambar di atas adalah dekat dari putaran, sehingga
skor untuk putaran pergelangan tangan adalah 2.
Masing-masing skor postur tubuh di atas dimasukkan ke dalam tabel A, yaitu sebagai
berikut:
Skor lengan atas
Skor lengan bawah
Skor pergelangan
tangan
Skor putaran
pergelangan tangan
Skor tubuh grup A gambar di atas adalah 4. Skor tersebut kemudian ditambahkan dengan
skor aktivitas dan skor beban.
a. Skor aktivitas untuk gambar di atas adalah 1 karena postur saat menyusui adalah merupakan
postur statis.
b. Skor beban pada gambar di atas adalah 2 karena berat beban objek adalah 4,54 kg dan postur
statis serta dilakukan berulang-ulang.
Jadi, skor tubuh grup A + skor aktivitas + skor beban = 4 + 1 + 2 = 7
2. Skor Tubuh Grup B
a. Postur Leher
Sudut yang dibentuk adalah sebesar 25 derajat dan leher menekuk, sehingga skor untuk
postur leher adalah 3 + 1 = 4
b. Postur Batang Tubuh
Sudut yang dibentuk adalah sebesar 0 derajat dan tidak terdapat sandaran. Selain itu,
posisi punggung ibu membungkuk, sehingga skor untuk postur batang tubuh adalah 2 + 1
= 3.
c. Postur Kaki
Kaki ibu pada gambar di atas berada pada posisi normal, sehingga skor untuk postur kaki
adalah 1.
Masing-masing skor postur tubuh di atas dimasukkan ke dalam tabel A, yaitu sebagai
berikut:
Skor tubuh grup A gambar di atas adalah 6. Skor tersebut kemudian ditambahkan dengan
skor aktivitas dan skor beban.
Skor leher
Skor batang
tubuh
Skor kaki
a. Skor aktivitas untuk gambar di atas adalah 1 karena karena postur saat menyusui adalah
merupakan postur statis.
b. Skor beban pada gambar di atas adalah 2 karena berat beban objek adalah 4,54 kg dan postur
statis serta dilakukan berulang-ulang.
Jadi, skor tubuh grup A + skor aktivitas + skor beban = 6 + 1 + 2 = 9
Skor A dan Skor B dimasukkan ke dalam tabel C berikut:
Diperoleh skor akhir RULA gambar di atas adalah 7, sehingga responden pada gambar di
atas berada pada level risiko tinggi dan dibutuhkan tindakan sekarang juga untuk mengurangi
risiko dan meminimalisir akibat dari risiko lebih lanjut.
Skor A
Skor B
SCORES
+1 +2
+3 +4
+2 +
RULA Employee Assessment Worksheet based on RULA: a survey method for the investigation of work-related upper limb disorders, McAtamney & Corlett, Applied Ergonomics 1993, 24(2), 91-99
Wrist Twist Score
+3 +4 +1 +2
Step 9: Locate Neck Position: Step 9a: Adjust… If neck is twisted: +1 If neck is side bending: +1 Step 10: Locate Trunk Position:
Step 10a: Adjust… If trunk is twisted: +1 If trunk is side bending: +1
Step 11: Legs: If legs and feet are supported: +1 If not: +2
Step 12: Look-up Posture Score in Table B: Using values from steps 9-11 above, locate score in Table B
Step 13: Add Muscle Use Score If posture mainly static (i.e. held>10 minutes), Or if action repeated occurs 4X per minute: +1 Step 14: Add Force/Load Score If load < .4.4 lbs (intermittent): +0 If load 4.4 to 22 lbs (intermittent): +1 If load 4.4 to 22 lbs (static or repeated): +2 If more than 22 lbs or repeated or shocks: +3 Step 15: Find Column in Table C Add values from steps 12-14 to obtain Neck, Trunk and Leg Score. Find Column in Table C.
+1 +2
Add +1
+1 +2 +3 Add +1
A. Arm and Wrist Analysis B. Neck, Trunk and Leg Analysis
Step 1: Locate Upper Arm Position: Step 1a: Adjust… If shoulder is raised: +1 If upper arm is abducted: +1 If arm is supported or person is leaning: -1 Step 2: Locate Lower Arm Position: Step 2a: Adjust… If either arm is working across midline or out to side of body: Add +1 Step 3: Locate Wrist Position:
Step 3a: Adjust… If wrist is bent from midline: Add +1 Step 4: Wrist Twist: If wrist is twisted in mid-range: +1 If wrist is at or near end of range: +2 Step 5: Look-up Posture Score in Table A: Using values from steps 1-4 above, locate score in Table A Step 6: Add Muscle Use Score If posture mainly static (i.e. held>10 minutes), Or if action repeated occurs 4X per minute: +1
Step 7: Add Force/Load Score If load < .4.4 lbs (intermittent): +0 If load 4.4 to 22 lbs (intermittent): +1 If load 4.4 to 22 lbs (static or repeated): +2 If more than 22 lbs or repeated or shocks: +3
Step 8: Find Row in Table C Add values from steps 5-7 to obtain Wrist and Arm Score. Find row in Table C.
Upper Arm Score
Lower Arm Score
Wrist Score
Posture Score A
Muscle Use Score
Force/Load Score
Wrist & Arm Score
+1 +2 +3
+4
Posture Score B
Force/Load Score
Neck, Trunk & Leg Score
Muscle Use Score
Neck Score
Trunk Score
Leg Score
Final Score
Scoring: (final score from Table C) 1 or 2 = acceptable posture 3 or 4 = further investigation, change may be needed 5 or 6 = further investigation, change soon 7 = investigate and implement change
Task name: ________________________________ Reviewer:__________________________ Date: _______/_____/_____ provided by Practical Ergonomics
This tool is provided without warranty. The author has provided this tool as a simple means for applying the concepts provided in RULA . © 2004 Neese Consulting, Inc [email protected] (816) 444-1667
Table A: Wrist Posture Score 1 2 3 4
Upper Arm
Lower Arm
Wrist Twist
Wrist Twist
Wrist Twist
Wrist Twist
1 2 1 2 1 2 1 2
1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4
2 1 2 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5
3 1 3 3 4 4 4 4 5 5 2 3 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 5 5 5
4 1 4 4 4 4 4 5 5 5 2 4 4 4 4 4 5 5 5 3 4 4 4 5 5 5 6 6
5 1 5 5 5 5 5 6 6 7 2 5 6 6 6 6 7 7 7 3 6 6 6 7 7 7 7 8
6 1 7 7 7 7 7 8 8 9 2 8 8 8 8 8 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9
Table B: Trunk Posture Score Neck 1 2 3 4 5 6
Posture Legs Legs Legs Legs Legs Legs
Score 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1 1 3 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7
2 2 3 2 3 4 5 5 5 6 7 7 7
3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7
4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8
5 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8
6 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
1 2 3 4 5 6 7+ 1 1 2 3 3 4 5 5
2 2 2 3 4 4 5 5 3 3 3 3 4 4 5 6 4 3 3 3 4 5 6 6 5 4 4 4 5 6 7 7 6 4 4 5 6 6 7 7 7 5 5 6 6 7 7 7
8+ 5 5 6 7 7 7 7
Table C: Neck, trunk and leg score
Wris
t an
d Ar
m S
core