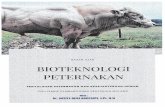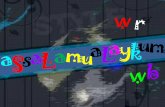Laporan Bioteknologi Kultur Jaringan
Transcript of Laporan Bioteknologi Kultur Jaringan
LAPORAN
PRAKTIKUM BIOTEKNOLOGI
Acara III
(Kultur Organ)
Oleh
Winda Dwi Astuti
NIM. 110210153015
Program Studi Pendidikan Biologi
LABORATORIUM KULTUR JARINGAN TUMBUHAN
BAB 1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Program revitalisasi yang digalakkan mulai tahun
2010 dapat diprediksi membutuhkan bahan tanam sekitar
50 juta dalam hal peremajaan, proses rehabilitasi dan
perluasan areal yang diharapkan. Hal ini ikut serta
diiringi dengan faktor diluar kebutuhan revitalisasi,
sehingga diperlukan bahan tanam sekitar 80 juta pada
tahun 2010. Namun hal ini sangat kontras dengan teknik
konvensional yang telah dilakukan oleh beberapa ahli
yang hanya bisa menyediakan bahan tanam sekitar 35-50
juta pada setiap tahunnya. Oleh karena itu untuk
memenuhi kebutuhan akan bahan tanam maka perlu
ditambahkan suatu alternatif yang dapat digunakan dalam
proses perbanyakan, yaitu teknik kultur jaringan
(Wahyudi et al dalam Sholeh, 2011).
Teknik untuk mengatasinya dengan menggunakan
teknik kultur jaringan dengan tahap organogenesis.
Sebelumnya dapat diperjelas dari pengertian kultur
jaringan yang merupakan suatu teknik untuk mendapatkan
tanaman dalam jumlah yang besar dalam waktu yang
relatif lebih singkat serta dapat dipastikan bebas dari
virus dan penyakit. Multiplikasi atau perbanyakan yang
diperoleh melalui penanaman secara in vitro sangat
tinggi. Produksi bibit yang berkualitas, hasil yang
homogen, dan dalam waktu yang singkat dapat diperoleh
jumlah yang sangat banyak juga dapat diperoleh melalui
teknik budidaya konvensional (Hobir et al dalam Anna,
2013).
Perbanyakan yang diperoleh menggunakan teknik
kultur jaringan dapat menghasilkan tanaman yang seragam
hal ini dikarenakan perbanyakan yang dilakukan
dipengaruhi beberapa faktor yang diantaranya dapat
mempengaruhi inisiasi akar dan pertumbuhan kultur
jaringan yaitu garam mineral, auksin, gula, suhu, dan
cahaya, pertumbuhan dan morfogenesis tanaman secara
kultur jaringan dapat dikendalikan dengan keseimbangan
yang diperoleh dari interaksi zat pengatur tumbuh (ZPT)
dalam eksplan dan juga media yang dipergunakan (Dwi,
2010).
Kultur jaringan secara klonal dapat menggunakan
eksplan bunga, akar, dan daun serta embrio zigotik. Hal
ini dikarenakan faktor yang sangat berperan dalam
perbanyakan dengan eksplan embrio adalah umur dari
embrio yang digunakan sebagai eksplan. Karena semakin
kecil ukuran embrio maka jaringan meristematiknya juga
semakin muda. Oleh karena itu dalam hal ini planlet
dapat diperoleh dari jaringan embrio zigotik muda yang
berumur 120-150 hari (Lopez dalam Sholeh, 2011). Dalam
praktikum kultur jaringan ini yang bertujuan untuk
mengetahui organ yang dapat digunakan dalam proses
kultur jaringan yang salah satunya diperuntukkan pada
daun tembakau yang dapat diamati pada hari ke-7 dan
hari ke-14. Dalam hal ini maka dapat disajikan melalui
grafik pertumbuhan bahan tanam tembakau untuk
mengetahui proses pertumbuhan yang dapat dilihat selama
proses pengamatan.
1.2 Tujuan
1. Mengetahui organ tanaman yang mampu beregenerasi
menjadi tanaman lengkap
2. Mendapatkan eksplan yang steril
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
Kultur jaringan dapat mempergunakan bahan tanam
berupa tunas lateral. Hal ini mengacu pada salah satu
konsep dasar yang mendasari teknik kultur jaringan
yaitu organ yang digunakan dalam kultur jaringan harus
mempunyai sifat totipotensi. Sifat totipotensi adalah
kemampuan masing-masing sel dalam hal tumbuh dan
beregenerasi menjadi tanaman lengkap yang disertai
dengan kondisi lingkungan yang memadai. Maka dari itu
eksplan yang digunakan berasal dari jaringan yang masih
muda (juvenil) yang dikarenakan dapat mudah tumbuh dan
beregenerasi dibandingkan jaringan yang sudah mature
atau sudah mengalami diferensiasi lanjut. Jaringan muda
yang digunakan memiliki sifat sel yang sangat aktif
membelah dengan dinding sel yang masih belum kompleks.
Jaringan muda yang sering digunakan antara lain: pucuk
muda, kuncup muda, hipokotil, inflorescence yang belum
dewasa.
Penggunaan tunas lateral juga dapat digunakan
sebagai eksplan yang bertujuan untuk mendapatkan organ
dengan jaringan yang masih bersifat meristematik,
artinya jaringan tersebut masih aktif membelah.
Disamping kultur pucuk yang telah berkembang pada tahun
60-an, berdasarkan Yuliarti (2010: 46) kultur dapat
digunakan dalam bermacam-macam kultur yaitu kultur
organ yang bersumber dari eksplan yang dapat berasal
dari bagian organ tanaman seperti tunas, akar, batang,
biji, umbi, daun, dan tangkai daun. Kultur meristem
yang menggunakan eksplan dari tunas pucuk atau tunas
aksiler, dan juga ruas batang.
Kultur sel yang mempunyai tipe khusus seperti
serbuk sari (sel haploid) dan endosperm dengan sel
triploid. Setelah itu, kultur anter atau polen yang
menggunakan eksplan dari anter atau kepala sari yang
mengandung polen. Kultur embrio bertujuan memperpendek
waktu berkecambah, menguji kecepatan viabilitas biji,
memperbanyak tanaman langka yang mempunyai embrio pada
keadaan normal sering mati pada awal tingkat
perkembangannya. Langkah dalam kultur embrio dengan
memisahkan embrio yang masih belum dewasa dan
menumbuhkannya secara in vitro.
Kultur protoplas yang bertujuan untuk mempelajari
komponen penyusun sel atau organel hingga dapat
melakukan fusi protoplas. Selain itu juga untuk
mendapatkan tanaman hybrid dan cybrid somatic yang
dapat digunakan dalam transplantasi dan transformasi
genetik. Kultur biji yang mempercepat waktu untuk
berkecambah dan mengatasi masalah pada tanaman langka,
mempelajari kecepatan pertumbuhan hingga diperoleh biji
steril untuk mengatasi kontaminasi yang terjadi pada
eksplan yang dibudidayakan.
Keberhasilan kultur jaringan sangat dipengaruhi
oleh zat pengatur tumbuh tanaman. Zat pengatur tumbuh
ini mempengaruhi pertumbuhan dan morfogenesis dalam
kultur sel, jaringan dan organ. Zat pengatur tumbuh
dapat digolongan menjadi beberapa golongan, yaitu
auksin, sitokinin, giberelin, dan inhibitor. Hal ini
dikarenakan interaksi dan perimbangan antara zat
pengatur tumbuh yang diberikan dalam media dan yang
diproduksi oleh sel secara endogen, menentukan arah
perkembangan suatu kultur (Gunawan, 1988 dalam Anna,
2013).
Inisiasi tunas dapat dirangsang dengan penambahan
zat pengatur tumbuh golongan sitokinin seperti
benzilamino purin (BAP), Rinosil, Kinetin, Zeatin. Zat
pengatur tumbuh sitokinin yang berperan dalam
pengaturan pembelahan sel dan morfogenesis. Fungsi dari
aktivitas utama sitokinin adalah untuk mendorong
pembelahan sel, menginduksi pembentukan tunas adventif
dan dalam konsentrasi tinggi menghambat inisiasi akar.
Namun sitokinin juga aktif menghambat perombakan
protein dan klorofil dan menghambat penuaan
(senescence) (Gunawan, 1988 dalam Anna, 2013).
Sedangkan zat pengatur tumbuh yang termasuk
golongan auksin yaitu, Indol Asam Asetat (IAA), Indol
Asam Butirat (IBA), Naftalen Asam Asetat (NAA), dan 2,4
D Dikhlorofenoksiasetat. Hormon auksin menjadi dasar
penggunaan jaringan meristem sebagai eksplan, karena
jaringan ini terdapat banyak sekali hormone yang
mengatur pembelahan sehingga keadaan jaringan ini
selalu membelah. Golongan zat pengatur tumbuh dari
giberelin antara lain adalah GA1, GA2, GA3, dan GA4.
Sedangkan golongan inhibitor terdiri atas fenolik dan
asam absisat (Hendaryono, 1994: 18).
Dalam setiap teknik kultur jaringan menggunakan
zat pengatur tumbuh auksin yaitu NAA dan 2,4 D yang
mempunyai sifat lebih stabil dibandingkan dengan IAA,
karena IAA dapat mengalami degradasi oleh adanya cahaya
ataupun dapat diuraikan oleh enzim oksidatif (Dods
dalam Hendaryono, 1994:20). Sedangkan keunggulan dari
NAA dan 2,4 D tidak mudah terurai oleh enzim-enzim yang
dikeluarkan oleh sel atau pemanasan pada saat proses
sterilisasi (Gamborg dalam Hendaryono, 1994: 21).
Auksin yang pada umumnya berfungsi untuk memacu
pembelahan sel, pemanjangan sel dan berperan dalam
pengakaran. NAA dan BAP merupakan jenis zat pengatur
tumbuh yang sering digunakan dalam kultur jaringan.
BAP golongan sitokinin sering digunakan bersamaan
dengan NAA untuk mendapatkan morfogenesis tanaman yang
diinginkan. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya akar,
tinggi planlet, jumlah daun, jumlah tunas, dan jumlah
akar. Media yang digunakan mampu mendorong
organogenesis pertumbuhan. Sehingga menunjukkan adanya
keseimbangan antara hormon endogen dan zat pengatur
tumbuh yang diberikan pada setiap perlakuan guna
mendorong proses organogenesis. Pertumbuhan dan
perkembangan eksplan dipengaruhi oleh interaksi dan
keseimbangan antara zat pengatur tumbuh endogen dan zat
pengatur tumbuh eksogen (Mirni, 2011).
Pertumbuhan juga memerlukan pembentukan senyawa
bahan baku dinding sel. Pembuatan komponen-komponen ini
dan penyusunan kembali ke dalam suatu matriks yang utuh
dipengaruhi oleh auksin, dengan jalan mengaktifkan
enzim yang berperan dalam pembentukan dinding sel
(Wattimena, 1991 dalam Anna, 2013). Sel dapat
mengembang dengan berbagai cara. Salah satunya
dikarenakan beberapa bahan osmotik seperti gula, dapat
diangkut masuk ke vakuola. Air akan masuk ke sel dan
dinding sel akan mengembang sampai suatu tekanan
dinding sel tertentu yang dapat menghalangi masuknya
air selanjutnya. Dinding sel yang retak diakibatkan
oleh pengembangan sel ini diperbaiki dengan penambahan
atau pembentukan bahan dinding sel yang baru (Noggle
dan Fritz, 1983 dalam Anna, 2013).
Pertumbuhan berkaitan dengan pertambahan volume
dan jumlah sel, pembentukan protoplasma, pertambahan
berat dan selanjutnya terjadi pertambahan berat kering.
Pengeringan bertujuan untuk menghentikan metabolisme
sel dari bahan tersebut (Sitompul dan Guritno, 1995
dalam Reynold, 2010). Gunawan dkk. (1992) mengemukaan
bahwa berat kering yang dihasilkan dalam hal ini berat
kering kalus tergantung dari kecepatan sel-sel tersebut
untuk membelah diri, memperbanyak diri, yang
dilanjutkan dengan pembesaran sel. Kecepatan sel
membelah ini dapat dipengaruhi oleh adanya hormon
tumbuh seperti auksin dan sitokinin. Hal ini diduga
dengan penambahan kedua hormon tersebut dapat
mempengaruhi metabolisme RNA yang berperan dalam
sintesis protein melalui proses transkripsi molekul
RNA. Kenaikan sintesis protein sebagai sumber tenaga
dapat digunakan untuk pertumbuhan sehingga dapat
meningkatkan berat kering dari tanaman (Marlin, 2012).
ZPT yang sering digunakan untuk menstimulasi
pembentukan kalus dari golongan auksin adalah 2,4-D.
Umumnya auksin meningkatkan pemanjangan sel, pembelahan
sel, dan pembentukan akar adventif, dalam medium kultur
auksin dibutuhkan untuk meningkatkan embryogenesis
somatic pada kultur suspense sel. Konsentrasi auksin
yang tinggi akan merangsang pembentukan kalus dan
menekan morfogenesis (George dan Sherrington, 1984
dalam Marlin, 2012). Kalus merupakan sumber bahan
tanam yang sangat penting dalam meregenerasi tanaman
yang baru. Penggunaan kalus akan sangat menguntungkan
karena pembentukan kalus dapat diinisiasi dari jaringan
manapun dari tanaman. Pembengkakan eksplan yang terjadi
adalah sebagai respon dari tanaman yang mengakibatkan
sebagian besar karbohidrat dan protein yang ada akan
terakumulasi pada jaringan yang luka (Barahima, 2012).
Faktor lain dalam hal mempengaruhi keberhasilan
teknik kultur jaringan menggunakan kultur organ yaitu
adalah lingkungan tumbuh dengan beberapa parameter
lingkungan yang ada dalam botol kultur terhadap
pertumbuhan talus atau tunas, antara lain: suhu,
kelembaban dan cahaya. Tanaman umumnya dapat tumbuh
pada lingkungan dengan suhu yang sama di setiap proses
pertumbuhannya. Dapat dimisalkan bahwa suhu pada siang
hari dengan malam hari sangatlah berbeda sehingga
tanaman mengalami perbedaan kondisi suhu yang lumayan
cukup besar. Oleh karena itu, dalam laboratorium kultur
in vitro dapat diatur dengan suhu yang selalu konstan
yang tidak lebih tinggi dari suhu pada kondisi in vivo.
Suhu yang dipergunakan dalam laboratorium suhu 21-25°C.
Tanaman tropis dapat dikulturkan pada suhuyang lebih
tinggi dari tanaman empat musim sekitar 27°C (24-32°C)
(Yuliarti, 2010: 50).
Kelembaban relative dalam botol kultur dengan
mulut botol yang ditutup dengan aluminium foil umumnya
diperoleh kelembaban yang tinggi antara 80-99%. Namun
apabila sudah ditutup tapi masih sedikit longgar maka
kelembaban relative dalam botol dapat lebih rendah dari
80%. Kelembaban di ruangan kultur berada pada
kelembaban relative dibawah 70% dapat mengakibatkan
botol kutur yang tidak tertutup rapat dapat cepat
menguap dan kering sehingga eksplan dan planlet yang
dikulturkan akan kehilangan nutrisi yang terkandung
pada media. Kelembaban udara relatif yang tinggi dalam
botol kultur juga tidak baik untuk eksplan dan planlet
dikarenakan menyebabkan tanaman dapat tumbuh abnormal
dengan daun yang lemah, mudah patah, tanaman kecil-
kecil sehingga kondisi ini disebut vitrifikasi atau
hiperhidrocity (Yusnita dalam Mirni, 2011).
Pada teknik perbanyakan tanaman secara in vitro,
kultur umumnya diinkubasikan pada sebuah ruang
penyimpanan dengan penyinaran yang cukup. Hal ini
dikarenakantunas umumnya dapat dirangsang
pertumbuhannya dengan adanya penyinaran. Sumber cahaya
yang biasanya digunakan dalam ruangan kultur jaringan
adalah lamu fluorescent (TL) yang dapat menghasilkan
warna putih, selain itu suhu ruang kultur dapat
meningkat namun dalam jumlah yang sedikit. Intesitas
yang digunakan dalam ruang kultur sekitar 1/10 dari
intensitas cahaya yang dibutuhkan dalam keadaan normal.
Intensitas yang digunakan untuk pertumbuhan tunas
sekitar 600-1000 lux. Sedangkan pada tahap
perkecambahan dan inisiasi akar hanya dapat dilakukan
pada intensitas cahaya yang lebih sedikit dibandingkan
dengan pertumbuhan tunas (Triningsih, 2013). Oleh
karena itu kuantitas dan kualitas dari cahaya, lama
waktu penyinaran, dan panjang gelombang cahaya dapat
mempengaruhi pertumbuhan eksplan dalam kultur in vitro
disamping adanya suhu dan kelembaban relatif udara.
BAB 3. METODE PRAKTIKUM
3.1 Waktu dan Tempat
Praktikum Kultur Jaringan Tumbuhan dengan acara
Kultur Organ dilaksanakan pada hari Minggu, 11 Mei 2014
pukul 12.00 s/d selesai bertempat di Laboratorium
Kultur Jaringan Tumbuhan Jurusan Budidaya Pertanian,
Fakultas Pertanian, Universitas Jember.
3.2 Alat dan Bahan
3.2.1 Alat
1. Laminar Air Flow (LAF)
2. Botol semprot
3. Pinset
4. Pisau
5. Seal (segel)
6. Kertas label
7. Alat tulis
8. Bunsen
9. Petridish
3.2.2 Bahan
1. Medium padat kultur jaringan yang telah dibuat
pada praktikum sebelumnya dengan 5 macam perlakuan
2. Kultur tembakau dalam botol kultur
3. Pestisida/ Fungisida
4. Aquades
5. Alkohol 70%
3.3 Prosedur Kerja
Bahan tanam Tembakau disamakan berdasarkan praktikum
yang telah dilakukan
1. Membuka plastik yang membungkus petridish yang
sebelumnya telah disterilkan menggunakan
autoclave, mensterilkan di atas nyala api Bunsen
2. Menjaga agar alat tetap steril maka sebelum
digunakan memanaskan terlebih dahulu di atas nyala
api Bunsen
3. Mengangin-anginkan peralatan yang telah steril
sebelum masuk dalam botol kultur
4. Mengeluarkan kultur dari dalam botol dengan sangat
hati-hati agar merusak kultur
5. Meletakkan kultur pada petridish menggunakan
pinset steril
6. Setelah meletakkan kultur pada petridish pinset
yang telah digunakan harus disterilkan kembali
sebelum digunakan lagi.
7. Mensterilkan dahulu Pisau dan Pinset yang hendak
digunakan dengan nyala api pada Bunsen
8. Memotong kultur tembakau tepat pada bagian daun
yang masih muda dan sehat
9. Memotong daun yang utuh menjadi 2 bagian yang sama
dan begitu pula seterusnya hingga di dapatkan
jumlah yang diharapkan
10. Mensterilkan kembali potongan yang telah di
dapatkan beserta petridishnya
11. Sebelum dibuka, maka hendaklah
mensterilkannya dalam nyala api pada Bunsen
12. Mengambil beberapa potongan daun tembakau
13. Meletakkan potongan daun (menanam potongan
daun) yang telah di ambil ke dalam botol kultur
yang telah disediakan hingga tepat pada medium
14. Setelah selesai menanam atau meletakkan
kultur pada media media tersebut harus ditutup
kembali dengan aluminium foil
15. Memasang kembali karet gelang pada leher
botol kutur agar tidak ada rongga udara pada botol
untuk mencegah kontaminan
16. Untuk mengunci media agar tidak terpengaruh
dari luar atau mendapat kontaminan dari luar
selain dileher botol dipasang karet gelang harus
di seal atau di segel lagi
17. Mengamati kultur pada hari ke-7 dan ke-14
3.4 Parameter Pengamatan
1. Mengamati perubahan yang terjadi pada bahan tanam.
Perubahan dapat ditunjukkan dengan adanya proses
pertumbuhan pada bahan tanam baik dalam bentuk
kalus, akar atau tunas.
2. Membuat grafik yang menyatakan pertubuhan kalus,
tunas, dan akar.
Tabel 1. Pertumbuhan Bahan Tanam Tembakau
Zat
Pengat
ur
Tumbuh
Bahan Tanam TembakauHari ke-7 Hari ke-14
Kalus Tunas Akar Kalus Tuna
sAkar
MS = 0 1 1 1NAA
0,25
ppm
dan
BAP 1
ppm
1 2 1
NAA 1
ppm
1 1 1
dan
BAP
0,25
ppmBAP
0,5
ppm1 2 1
2,4 D
0,5
ppm2 2 2 dst dst dst
Gambar 1. Grafik Pertumbuhan Tembakau pada hari ke-7
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil PengamatanTabel 1. Pertumbuhan Bahan Tanam Tembakau
Zat
Pengat
ur
Tumbuh
Bahan Tanam TembakauHari ke-7 Hari ke-14Kalus Tunas Akar Kalus Tuna
sAkar
MS = 0 0 0 0 0 0 0NAA
0,25
ppm
0 0 0 0 0 0
dan
BAP 1
ppmNAA 1
ppm
dan
BAP
0,25
ppm
0 0 0 0 0 0
BAP
0,5
ppm
0 0 0 0 0 0
2,4 D
0,5
ppm
0 0 0 0 0 0
Pertumbuhan Tembakau dalam grafik
Gambar 1. Grafik Pertumbuhan Tembakau pada hari ke-7
Gambar 2. Grafik Pertumbuhan Tembakau pada hari ke-14
4.2 Pembahasan
Pada praktikum kultur jaringan dengan acara kultur
organ yang bertujuan untuk mengetahui organ tanaman
yang mampu beregenerasi menjadi tanman lengkap dan
untuk mendapatkan eksplan yang steril. Alat yang
digunakan dalam praktikum ini sama dengan praktikum
teknik aseptik karena dilakukan pada waktu yang
bersamaan yaitu, Laminar Air Flow (LAF), Botol semprot
yang berisi alkohol 70%, Pinset, Pisau, Seal wrap
(segel), Kertas label, Alat tulis, Bunsen dan Petri
dish. Sedangkan bahan yang harus disediakan yaitu
medium padat kultur jaringan yang telah dibuat pada
praktikum sebelumnya, Pestisida/ Fungisida, Aquades
serta Alkohol 70%.
Setelah alat dan bahan sudah lengkap tersedia,
maka praktikan dapat memulai praktikum acara kultur
organ dengan prosedur yang sudah terdapat dalam modul
yaitu membuka plastik yang membungkus petridish yang
sebelumnya telah disterilkan menggunakan autoclave,
mensterilkan di atas nyala api Bunsen. Menjaga agar
alat tetap steril maka sebelum digunakan memanaskan
terlebih dahulu di atas nyala api Bunsen. Mengangin-
anginkan peralatan yang telah steril sebelum masuk
dalam botol kultur. Mengeluarkan kultur dari dalam
botol dengan sangat hati-hati agar merusak kultur.
Meletakkan kultur pada petridish menggunakan pinset
steril. Setelah meletakkan kultur pada petridish pinset
yang telah digunakan harus disterilkan kembali sebelum
digunakan lagi. Mensterilkan dahulu Pisau dan Pinset
yang hendak digunakan dengan nyala api pada Bunsen.
Memotong kultur tembakau tepat pada bagian daun
yang masih muda dan sehat. Memotong daun yang utuh
menjadi 2 bagian yang sama dan begitu pula seterusnya
hingga di dapatkan jumlah yang diharapkan. Mensterilkan
kembali potongan yang telah di dapatkan beserta
petridishnya Sebelum dibuka, maka hendaklah
mensterilkannya dalam nyala api pada Bunsen. Mengambil
beberapa potongan daun tembakau. Meletakkan potongan
daun (menanam potongan daun) yang telah di ambil ke
dalam botol kultur yang telah disediakan hingga tepat
pada medium. Setelah selesai menanam atau meletakkan
kultur pada media media tersebut harus ditutup kembali
dengan aluminium foil. Memasang kembali karet gelang
pada leher botol kutur agar tidak ada rongga udara pada
botol untuk mencegah kontaminan. Untuk mengunci media
agar tidak terpengaruh dari luar atau mendapat
kontaminan dari luar selain dileher botol dipasang
karet gelang harus di seal atau di segel lagi.
Mengamati kultur pada hari ke-7 dan ke-14
Setelah praktikum selesai dilakukan maka
dilakukanlah pengamatan pada hari ke-7 dan hari ke-14.
Parameter yang digunakan untuk mengamatinya adalah
mengamati perubahan yang terjadi pada bahan tanam.
Perubahan dapat ditunjukkan dengan adanya proses
pertumbuhan pada bahan tanam baik dalam bentuk kalus,
akar atau tunas. Pertumbuhan bahan tanam tembakau dapat
diperjelas dengan menggunakan grafik. Berdasarkan tabel
hasil pengamatan dapat diperoleh bahwasanya pada hari
ke-7 dan ke-14 menunjukkan hasil yang sama. Bahan tanam
tembakau yang telah ditanam dengan perlakuan MS=0
menunjukkan bahwa tidak ada perubahan bahan tanam baik
dari segi kalus = 0, tunas = 0, dan juga akar= 0.
Pada perlakuan MS dengan ZPT NAA 0,25ppm dan BAP
1ppm diperoleh hasil tidak ada perubahan bahan tanam
baik dari segi kalus = 0, tunas = 0, dan juga akar= 0.
Pada perlakuan selanjutnya dengan menggunakan media MS
yang di tambahi dengan ZPT NAA 1ppm dan BAP 0,25ppm
menunjukkan hal yang sama bahwa tidak ada perubahan
bahan tanam baik dari segi kalus = 0, tunas = 0, dan
juga akar= 0. Pada perlakuan ke-4 dengan media MS
menggunakan ZPT BAP 0,5ppm menunjukkan tidak ada
perubahan bahan tanam baik dari segi kalus = 0, tunas =
0, dan juga akar= 0. Perlakuan yang terakhir dengan
media MS yang ditambahi dengan 2,4 D 0,5 ppm tidak ada
perubahan bahan tanam baik dari segi kalus = 0, tunas =
0, dan juga akar= 0. Sehingga dapat disimpulkan
berdasarkan hasil pengamatan hari ke-7 dan hari ke-14
dapat diketahui tidak ada aktivitas pertumbuhan. Hal
ini dikarenakan tidak adanya perubahan yang dapat
dilihat dengan munculnya kalus, tunas, dan akar pada
eksplan. Oleh karena itu dapat diperjelas dalam grafik
pertumbuhan pada hari ke-7 dan hari ke-14.
Pada grafik pertumbuhan hari ke-14 juga diperoleh
grafik yang sama dengan grafik pertumbuhan pada hari
ke-7.
Berdasarkan grafik yang telah ditampilkan maka,
waktu pertumbuhan untuk bahan tanam tembakau
membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membentuk kalus
hingga menjadi tunas dan menjadi planlet dengan adanya
akar. Karena pada dasarnya kultur organ merupakan salah
satu teknik dalam hal perbanyakan tanaman dengan kultur
jaringan. Perbanyakan secara in vitro dapat dilakukan
melalui tiga cara yaitu pembentukan tunas adventif,
proliferasi tunas lateral, dan embriogenesis somatic
(Rossa, 2011).
Tidak hanya bahan tanam yang telah disebutkan
karena pada dasarnya kultur jaringan dapat dilakukan
dalam berbagai jenis berdasarkan Yuliarti (2010: 46)
kultur dapat digunakan dalam bermacam-macam kultur
yaitu kultur organ yang bersumber dari eksplan yang
dapat berasal dari bagian organ tanaman seperti tunas,
akar, batang, biji, umbi, daun, dan tangkai daun.
Kultur meristem yang menggunakan eksplan dari tunas
pucuk atau tunas aksiler, dan juga ruas batang. Kultur
sel yang mempunyai tipe khusus seperti serbuk sari (sel
haploid) dan endosperm dengan sel triploid. Setelah
itu, kultur anter atau polen yang menggunakan eksplan
dari anter atau kepala sari yang mengandung polen.
Kultur embrio bertujuan memperpendek waktu
berkecambah, menguji kecepatan viabilitas biji,
memperbanyak tanaman langka yang mempunyai embrio pada
keadaan normal sering mati pada awal tingkat
perkembangannya. Langkah dalam kultur embrio dengan
memisahkan embrio yang masih belum dewasa dan
menumbuhkannya secara in vitro. Kultur protoplas yang
bertujuan untuk mempelajari komponen penyusun sel atau
organel hingga dapat melakukan fusi protoplas. Selain
itu juga untuk mendapatkan tanaman hybrid dan cybrid
somatic yang dapat digunakan dalam transplantasi dan
transformasi genetik. Kultur biji yang mempercepat
waktu untuk berkecambah dan mengatasi masalah pada
tanaman langka, mempelajari kecepatan pertumbuhan
hingga diperoleh biji steril untuk mengatasi
kontaminasi yang terjadi pada eksplan yang
dibudidayakan.
Salah satu faktor keberhasilan kultur jaringan
sangat dipengaruhi oleh zat pengatur tumbuh tanaman.
Zat pengatur tumbuh ini mempengaruhi pertumbuhan dan
morfogenesis dalam kultur sel, jaringan dan organ. Zat
pengatur tumbuh dapat digolongan menjadi beberapa
golongan, yaitu auksin, sitokinin, giberelin, dan
inhibitor. Hal ini dikarenakan interaksi dan
perimbangan antara zat pengatur tumbuh yang diberikan
dalam media dan yang diproduksi oleh sel secara
endogen, menentukan arah perkembangan suatu kultur
(Gunawan, 1988 dalam Anna, 2013).
Hal ini dikarenakan pertumbuhan juga memerlukan
pembentukan senyawa bahan baku dinding sel. Pertumbuhan
berkaitan dengan pertambahan volume dan jumlah sel,
pembentukan protoplasma, pertambahan berat dan
selanjutnya terjadi pertambahan berat kering.
Pengeringan bertujuan untuk menghentikan metabolisme
sel dari bahan tersebut (Sitompul dan Guritno, 1995
dalam Reynold, 2010). Gunawan dkk. (1992) mengemukaan
bahwa berat kering yang dihasilkan dalam hal ini berat
kering kalus tergantung dari kecepatan sel-sel tersebut
untuk membelah diri, memperbanyak diri, yang
dilanjutkan dengan pembesaran sel. Kecepatan sel
membelah ini dapat dipengaruhi oleh adanya hormon
tumbuh seperti auksin dan sitokinin. Hal ini diduga
dengan penambahan kedua hormon tersebut dapat
mempengaruhi metabolisme RNA yang berperan dalam
sintesis protein melalui proses transkripsi molekul
RNA. Kenaikan sintesis protein sebagai sumber tenaga
dapat digunakan untuk pertumbuhan sehingga dapat
meningkatkan berat kering dari tanaman (Marlin, 2012).
Zat pengatur tumbuh yang digunakan pada praktikum
kultur organ kali ini adalah NAA (Naftalen Asam
Asetat), BAP (benzyl amino purin), dan 2,4 D. Naftalen
Asam Asetat (NAA), dan 2,4 D Dikhlorofenoksiasetat yang
termasuk zat pengatur tumbuh golongan auksin. Hormon
auksin menjadi dasar penggunaan jaringan meristem
sebagai eksplan, karena jaringan ini terdapat banyak
sekali hormone yang mengatur pembelahan sehingga
keadaan jaringan ini selalu membelah. (Hendaryono,
1994: 18).
ZPT golongan auksin 2,4-D yang digunakan untuk
menstimulasi pembentukan kalus dari. Umumnya auksin
meningkatkan pemanjangan sel, pembelahan sel, dan
pembentukan akar adventif, dalam medium kultur auksin
dibutuhkan untuk meningkatkan embryogenesis somatic
pada kultur suspense sel. Konsentrasi auksin yang
tinggi akan merangsang pembentukan kalus dan menekan
morfogenesis (George dan Sherrington, 1984 dalam
Marlin, 2012). Kalus merupakan sumber bahan tanam yang
sangat penting dalam meregenerasi tanaman yang baru.
Penggunaan kalus akan sangat menguntungkan karena
pembentukan kalus dapat diinisiasi dari jaringan
manapun dari tanaman. Pembengkakan eksplan yang terjadi
adalah sebagai respon dari tanaman yang mengakibatkan
sebagian besar karbohidrat dan protein yang ada akan
terakumulasi pada jaringan yang luka (Barahima, 2012).
Benzyl amino purin (BAP) termasuk ke dalam zat
pengatur tumbuh golongan sitokinin, yang berperan dalam
merangsang proses inisiasi tunas, pengaturan pembelahan
sel dan morfogenesis. Fungsi dari aktivitas utama
sitokinin adalah untuk mendorong pembelahan sel,
menginduksi pembentukan tunas adventif dan dalam
konsentrasi tinggi menghambat inisiasi akar. Namun
sitokinin juga aktif menghambat perombakan protein dan
klorofil dan menghambat penuaan (senescence) (Gunawan,
1988 dalam Anna, 2013).
BAP termasuk ke dalam golongan sitokinin sering
digunakan bersamaan dengan NAA untuk mendapatkan
morfogenesis tanaman yang diinginkan. Hal ini
ditunjukkan dengan munculnya akar, tinggi planlet,
jumlah daun, jumlah tunas, dan jumlah akar. Media yang
digunakan mampu mendorong organogenesis pertumbuhan.
Sehingga menunjukkan adanya keseimbangan antara hormon
endogen dan zat pengatur tumbuh yang diberikan pada
setiap perlakuan guna mendorong proses organogenesis.
Pertumbuhan dan perkembangan eksplan dipengaruhi oleh
interaksi dan keseimbangan antara zat pengatur tumbuh
endogen dan zat pengatur tumbuh eksogen (Mirni, 2011).
Faktor lain dalam hal mempengaruhi keberhasilan
teknik kultur jaringan menggunakan kultur organ yaitu
adalah pengaruh lingkungan tumbuh dengan beberapa
parameter lingkungan yang ada dalam botol kultur
terhadap pertumbuhan talus atau tunas, antara lain:
suhu, kelembaban dan cahaya. Tanaman umumnya dapat
tumbuh pada lingkungan dengan suhu yang sama di setiap
proses pertumbuhannya. Dapat dimisalkan bahwa suhu pada
siang hari dengan malam hari sangatlah berbeda sehingga
tanaman mengalami perbedaan kondisi suhu yang lumayan
cukup besar. Oleh karena itu, dalam laboratorium kultur
in vitro dapat diatur dengan suhu yang selalu konstan
yang tidak lebih tinggi dari suhu pada kondisi in vivo.
Suhu yang dipergunakan dalam laboratorium suhu 21-25°C.
Tanaman tropis dapat dikulturkan pada suhuyang lebih
tinggi dari tanaman empat musim sekitar 27°C (24-32°C)
(Yuliarti, 2010: 50).
Kelembaban relatif dalam botol kultur dengan mulut
botol yang ditutup dengan aluminium foil umumnya
diperoleh kelembaban yang tinggi antara 80-99%. Namun
apabila sudah ditutup tapi masih sedikit longgar maka
kelembaban relative dalam botol dapat lebih rendah dari
80%. Kelembaban di ruangan kultur berada pada
kelembaban relative dibawah 70% dapat mengakibatkan
botol kutur yang tidak tertutup rapat dapat cepat
menguap dan kering sehingga eksplan dan planlet yang
dikulturkan akan kehilangan nutrisi yang terkandung
pada media. Kelembaban udara relatif yang tinggi dalam
botol kultur juga tidak baik untuk eksplan dan planlet
dikarenakan menyebabkan tanaman dapat tumbuh abnormal
dengan daun yang lemah, mudah patah, tanaman kecil-
kecil sehingga kondisi ini disebut vitrifikasi atau
hiperhidrocity (Yusnita dalam Mirni, 2011).
Pada teknik perbanyakan tanaman secara in vitro,
kultur umumnya diinkubasikan pada sebuah ruang
penyimpanan dengan penyinaran yang cukup. Hal ini
dikarenakantunas umumnya dapat dirangsang
pertumbuhannya dengan adanya penyinaran. Sumber cahaya
yang biasanya digunakan dalam ruangan kultur jaringan
adalah lamu fluorescent (TL) yang dapat menghasilkan
warna putih, selain itu suhu ruang kultur dapat
meningkat namun dalam jumlah yang sedikit. Intesitas
yang digunakan dalam ruang kultur sekitar 1/10 dari
intensitas cahaya yang dibutuhkan dalam keadaan normal.
Intensitas yang digunakan untuk pertumbuhan tunas
sekitar 600-1000 lux. Sedangkan pada tahap
perkecambahan dan inisiasi akar hanya dapat dilakukan
pada intensitas cahaya yang lebih sedikit dibandingkan
dengan pertumbuhan tunas (Triningsih, 2013).
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dapat
disimpulkan bahwasanya lingkungan seperti suhu,
kelembaban relatif udara, kuantitas serta kualitas
cahaya yang disebut intensitas cahaya, lama penyinaran,
dan panjang gelombang dalam botol kultur sangat
berpengaruh terhadap pertumbuhan kalus, sebelum terjadi
pertumbuhan organ atau juga jaringan yang tidak
terpengaruh oleh beberapa parameter lingkungan yang ada
dalam botol kultur selama proses kultur jaringan.
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
1. Organ tanaman yang mampu beregenerasi menjadi
tanaman lengkap sehingga mempunyai sifat totipotensi.
Karena sifat tersebut tanaman dapat diperbanyak
dengan menggunakan teknik kultur jaringan. Maka dari
itu eksplan yang digunakan berasal dari jaringan yang
masih muda (juvenil) yang dikarenakan dapat mudah
tumbuh dan beregenerasi dibandingkan jaringan yang
sudah mature atau sudah mengalami diferensiasi
lanjut. Jaringan muda yang digunakan memiliki sifat
sel yang sangat aktif membelah dengan dinding sel
yang masih belum kompleks. Jaringan muda yang sering
digunakan antara lain: pucuk muda, kuncup muda,
hipokotil, inflorescence yang belum dewasa.
2. Eksplan yang steril dapat dihasilkan melalui
proses sterilisasi bahan tanam dengan menggunakan
bahan sterilisasi seperti Clorox atau bayclin
ditujukan karena bayclin memiliki kandungan yang
dapat membersihkan eksplan dari berbagai macam
kontaminan baik berupa jamur, virus, bakteri.
Sehingga pada eksplan yang steril dapat diperoleh
planlet murni atau stok murni tanaman dalam jumlah
yang besar dalam waktu yang relatif lebih singkat
serta dapat dipastikan bebas dari virus dan penyakit.
Multiplikasi atau perbanyakan yang diperoleh melalui
penanaman secara in vitro sangat tinggi. Produksi bibit
yang berkualitas, hasil yang homogen, dan dalam waktu
yang singkat dapat diperoleh jumlah yang sangat
banyak juga dapat diperoleh melalui teknik budidaya
konvensional (Hobir et al dalam Anna, 2013).
5.2 Saran
Dalam hal menaikkan keberhasilan pada praktikum
ini, adapun beberapa saran yang pastinya perlu untuk
diperhatikan, yaitu
1. Sangat memperhatikan kesterilan alat dan bahan dan
memastikan semuanya dalam keadaan steril.
2. Selalu memakai jas praktikum saat praktikum maupun
pada saat pengamatan baik pada praktikan maupun
asisten laboratorium untuk menghindari adanya
kontaminasi.
Anna Rufaida, Waeniaty, Muslimin, I NengahSuwastika. 2013. Organogenesis Tanaman BawangMerah (Allium ascalonicum L.) Lokal Palu Secara InVitro Pada Medium Ms Dengan Penambahan AnnaRufaida IAA dan BAP. Online Jurnal of Natural Science,Vol. 2 (2) ISSN: 2338-0950
Barahima Abbas, Florentina Heningtyas Listyorini,
Eko Agus Martanto, dan Yanuarius Renwarin. 2012.Pertumbuhan Jaringan Stipe dari Jamur Sagu(Volvariella sp) Endemik Papua dalam Kultur invitro Jurnal Natur Indonesia 14(3): 184-190 ISSN1410-9379
Dwi Wahyuni Ardiana dan Ida Fitrianingsih. 2010.
Teknik Kultur Jaringan Tunas Pepaya dengan
Menggunakan Beberapa Konsentrasi IBA. Dwi W Buletin
Teknik Pertanian Vol. 15, No. 2 :52-55
Hendaryono, Daisy P Sriyanti; Wijayanti, Ari. 1994.
Teknik Kultur Jaringan Cetakan ke-13. Yogyakarta:
Kanisius
Marlin, Yulian, dan Hermansyah. 2012. Inisiasi KalusEmbriogenik Pada Kultur Jantung Pisang ‘Curup’Dengan Pemberian Sukrosa, Bap Dan 2,4-D.Initiation of embryogenic callus formation of
Banana ‘Curup’ male bud culture supplementedwith sucrose, BAP, and 2,4-D. J. Agrivigor 11(2): 275-283,; ISSN 1412-2286
Mirni Ulfa Bustami. 2011. Penggunaan 2, 4-D Untuk Induksi Kalus Kacang Tanah. Media Litbang Sulteng IV (2): 137 – 141, ISSN: 1979 – 5971
Reynold P. Kainde dan Billi, Wagania. 2010. KajianPerkecambahan Benih Mahoni pada Beberapa MediaSecara In vitro. Eugenia Volume 16 Nomor 1.
Rossa Yunita, Endang dan Gati Lestarai. 2011.Perbanyakan Tanaman Pulai Pandak (Rauwolfiaserpentina L.) dengan Teknik Kultur Jaringan.Jurnal Natur Indonesia 14(1): 68-72 ISSN 1410-9379,Keputusan Akreditasi No 65a/DIKTI/Kep./2008
Sholeh Avivi, Didik Pudji Restanto, dan Tri
Widyastuti. 2011. Pengaruh Ukuran Embriozigot
terhadap Regenerasi Beberapa Klon Kakao. Jurnal
Natur Indonesia 13(3): 237-243 ISSN 1410-9379,
Keputusan Akreditasi No 65a/DIKTI/Kep.
Triningsih, Luthfi A. M Siregar, Lollie A. P. Putri.2013. Pertumbuhan Eksplan Puar Tenangau
(Elettariopsis Sp.) Secara In Vitro. Jurnal OnlineAgroekoteknologi Vol.1, No.2, ISSN No. 2337- 6597
Yuliarti, Nurheti. 2010. Kultur Jaringan Tanaman Skala
Rumah Tangga. Yogyakarta: Lily Publisher 1