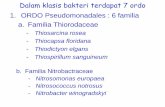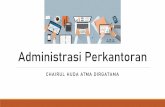Laporan agroklimat FP UNS 2014 Yeli Yulianti H0714153
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Laporan agroklimat FP UNS 2014 Yeli Yulianti H0714153
I. PENGENALAN ALAT DAN PENGAMATAN UNSUR-UNSUR CUACA
SECARA MANUAL
A. Pendahuluan1.Latar Belakang
Unsur-unsur cuaca merupakan faktor penting
dalam kehidupan, terutama di sektor pertanian.
Pengelolaan dan hasil pertanian sangat tergantung
terhadap unsur-unsur cuaca, seperti radiasi
matahari, tekanan udara, suhu, kelembaban, curah
hujan, angin, evaporasi, dan awan. Tanaman tak
dapat bertahan hidup dan menghasilkan produk yang
kurang baik dalam kondisi cuaca yang tak tentu.
Cuaca diartikan sebagai keadaan udara pada
suatu waktu di suatu tempat tertentu, sehingga
kondisi cuaca akan senantiasa berubah dari waktu
ke waktu. Cuaca dan iklim saling berhubungan,
karena iklim merupakan kondisi lanjutan dan
merupakan kumpulan dari kondisi cuaca yang
kemudian disusun dan dihitung dalam bentuk rata-
rata kondisi cuaca dalam kurun waktu tertentu.
Di Indonesia pengetahuan tentang cuaca dan
iklim adalah sangat penting karena sering adanya
penyimpangan permulaan musim penghujan yang
mempengaruhi kegiatan usaha tani di Indonesia.
Fluktuasi hasil pertanian juga dipengaruhi oleh
cuaca dan iklim. Walaupun suatu daerah pertanian
1
2
sangat subur dan dengan perawatan tanaman yang
maksimal, namun apabila cuaca dan iklimnya buruk
maka hasil produksinya pun tidak akan maksimal,
bahkan dapat mengalami kegagalan.
Oleh sebab itu, pengetahuan tentang iklim dan
cuaca perlu diperhatikan karena mempunyai peranan
yang penting di bidang pertanian. Karena hal
itulah, sebagai mahasiswa pertanian perlu juga
mengetahui unsur-unsur cuaca dengan melakukan
praktikum lapangan serta pengamatan secara
langsung untuk mengetahui keadaan cuaca.
2. Tujuan Praktikum
Acara pengenalan alat dan pengamatan unsur-unsur
cuaca secara manual cuaca ini dilaksanakan dengan
tujuan :
a. Mengetahui alat-alat pengukur unsur cuaca dan
cara penggunaannya
b. Mengetahui cara pengamatan menggunakan alat –
alat manual
3. Waktu dan Tempat Praktikum
Praktikum Mata Kuliah Agroklimatologi untuk
Acara 1 Pengenalan Alat dan Pengamatan Unsur – Unsur
secara Manual dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8
November 2014. Praktikum Agroklimatologi Acara 1
Pengenalan Alat dan Pengamatan Unsur – Unsur secara
Manual bertempat di Stasiun Klimatologi, Desa
Sukosari, Kecamatan Jumantono, Karanganyar.
3
B. TINJAUAN PUSTAKA
1. Radiasi Surya
Matahari adalah sumber utama untuk kejadian-
kejadian cuaca. Garis tengahnya 100 kali garis
tengah bumi suhunya 60000 K. Jarak matahari ke
bumi 149.500.000 Km. Matahari memancarkan panasnya
ke bumi dengan jalan radiasi yang kecepatannya
sama dengan kecepatan sinar. Menurut hasil
penyelidikan dengan membuat spektrum dari sinar
matahari, maka sebagian dari sinar putih yang
mempunyai panjang gelombang 0.48 μ mempunyai
kekuatan penyinaran yang tertinggi (Hardjodinomo
2007).
Radiasi surya merupakan unsur iklim/cuaca
utama yang akan mempengaruhi keadaan unsur
iklim/cuaca lainnya. Perbedaan penerimaan radiasi
surya antar tempat di permukaan bumi akan
menciptakan pola angin yang selanjutnya akan
berpengaruh terhadap kondisi curah hujan, suhu
udara, kelembaban nisbi udara, dan lain-lain.
Pengendali iklim suatu wilayah akan sangat berbeda
dari pengendali iklim di bumi secara menyeluruh.
Kondisi iklim/cuaca akan mempengaruhi proses-
proses fisika, kimia, biologi, ekofisiologi, dan
kesesuaian ekologi dari komponen lingkungan yang
ada (LIPI 2008).
4
Semakin lama matahari memancarkan sinarnya di
suatu daerah, maka akan semakin banyak panas yang
diterima. Keadaan atmosfer yang cerah sepanjang
hari akan lebih panas daripada jika hari itu
berawan sejak pagi. Suatu tempat dengan posisi
matahari berada tegak lurus diatasnya, maka
radiasi matahari yang diberikan akan lebih besar,
dibandingkan dengan tempat yang posisi mataharinya
lebih miring (BMKG 2009).
Penerimaan radiasi surya di permukaan bumi
sangat bervariasi menurut tempat dan waktu.
Menurut tempat disebabkan oleh perbedaan letak
lintang serta keadaan atmosfer terutama awan.
Menurut waktu, perbedaan radiasi terjadi dalam
sehari (dari pagi sampai sore) maupun secara
musiman (Glen dan Lyle 2008).
Radiasi surya terdiri dari spectra ultraviolet
(panjang gelombang kurang dari 0.38 mikron) yang
berpengaruh merusak karena daya bakarnya sangat
tinggi, spectra Photosynthetically Active Radiation (PAR)
yang berperan membangkitan proses fotosintesis dan
spectra inframerah (lebih dari 0.74 mikron) yang
merupakan pengatur suhu udara . spectra radiasi
PAR dapat dirinci lebih lanjut menjadi pita-pita
spectrum yang masing-masing memiliki karakteristik
tertentu. Ternyata spectrum biru memberikan
5
sumbangan yang paling potensial dalam fotosintesis
(Koesmaryono 2008).
2. Tekanan Udara
Tekanan udara adalah tekanan yang diberikan
oleh udara, karena geraknya tiap 1 cm2 bidang
mendatar dari permukaan bumi sampai batas
atmosfer. Satuannya : 1 atm = 76 cmHg. Tekanan 1
atm disebut sebagai tekanan normal. Makin tinggi
tempat dari permukaan air laut (latitude) maka
tekanan udara makin menurun. Hal ini disebabkan
karena gradien tekanan udara vertikal (gradient
vertikal). Gradien vertikal ini tidak selalu tetap,
sebab kerapatan udara dipengaruhi oleh faktor :
suhu kadar uap air di udara dan gravitasi
(Wuryatno 2009).
Udara mempunyai massa/berat besarnya tekanan
diukur dengan barometer. Barograf adalah alat
pencatat tekanan udara. Tekanan udara dihitung
dalam milibar. Garis pada peta yang menghubunkan
tekanan udara yang sama disebut isobar. Barometer
aneroid sebagai alat pengukur ketinggian tempat
dinamakan altimeter yang biasa digunakan untuk
mengukur ketinggian pesawat terbang (Leonheart
2010).
Tekanan udara adalah berat massa udara pada
suatu wilayah. Perbedaan pemanasan matahari
mengakibatkan tekanan udara pada daerah satu
6
dengan daerah yang lain berbeda. Hal ini karena
pemanasan udara paling banyak terjadi pada
atmosfer bagian bawah. Jadi, semakin ke atas atau
tinggi suatu tempat semakin rendah tekanan
udaranya (Rahayu 2009).
Faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran
tekanan udara antara lain lintang bumi, lautan dan
daratan untuk menggambarkan tekanan udara suatu
daerah, ditarik garis-garis isobar. Garis ini
menggambarkan sebaran tekanan udara pada suatu
pereode tertentu. Tekanan udara selalu turun
dengan naiknya ketinggian (Hasan 2007).
Tekanan udara adalah tekanan yang diberikan
oleh udara, karena tiap 1 cm2 bidang mendatar dari
permukaan bumi sampai batas atmosfer. Satuannya
yaitu 1 atm 76 cmHg 760 mmHg. Semakin tinggi
tempat, tekanan udara akan berkurang, sebagai
ketentuan dapat dikemukakan bahwa setiap naik 300
m, maka tekanan udara akan turun 1/30 x. Tekanan
udara mengalir dari tempat bertekanan tinggi ke
tempat bertekanan lebih rendah. Penyebarannya bisa
secara vertikal maupun horizontal. Alat untuk
mengukur tekanan udara adalah barometer. Untuk
mengetahui tekanan udara pada suatu tempat juga
bisa dilakukan dengan melihat tabel tekanan udara
yang berdasarkan ketinggian tempat dari permukaan
laut
7
(Sumani 2013).
3. Suhu Udara
Suhu merupakan suatu konsep yang tidak mudah
untuk membuat batasan. Kita semua sadar akan suhu
dalam pengertian kualitatif untuk itu digunakan
dalam pernyataan dingin, panas, hangat dalam
pembicaraan sehari-hari. Jadi, suhu merupakan
derajat panas atau dingin sesuatu keadaan atau zat
(Soekardi 2008).
Suhu merupakan derajad panas atau dingin suatu
benda atau dapat dinyatakan sebagai energi kinetis
rata-rata suatu benda. Ada beberapa alat yan biasa
digunakan untuk melakukan pengamatan suhu udara,
antara lain termohigrograf berfungsi untuk
mengamati suhu dan kelembaban udara dalam bentuk
grafik, termohigrometer berguna untuk mengetahui
suhu sekaligus kelembaban udara, dalam pembacaan
angka, dan termometer maksimim dan minimum dalam
satu periode pengamatan (Sumani 2013).
Termometer maksimum dan minimum digunakan
untuk mengukur suhu permukaan, yang didefinikan
sebagai suhu didekat ketinggian mata pengamat
sekitar 1,5 m di atas permukaan tanah.pada alat
ini digunakan termometer zat cair dalam kaca.
Prinsip kerja termometer ini adalah jika suhu naik
maka zat cair akan memuai lebih cepat ketimbang
wadah kacanya. Termometer maksimum dan minimum
8
dapat menunjukkan suhu maksimum dan minimum dalam
jangka waktu tertentu dan suhu pada saat itu.
Termometer ini berbentuk pipa U yang pada kedua
ujungnya terdapat reservoir. Pada ujung yang satu,
reservoir berisi alkohol, sedangkan pada kaki yang
lainnya reservoir berisi alkohol sebagiannya dan
pada bagian atasnya terdapat uap alkohol. Bila
suhunya naik, reservoir memuai dan memdorong air
raksa. Stiff pada kaki yang lain terdorong ke atas
oleh air raksa. Jika suhunya turun, air raksa
dalam kaki pertama akan mendorong stiff ke atas.
Jadi suhu pada kaki yang satu menunjuk suhu
maksimum dan kaki yang lain menunjuk suhu minimum
(Marisa 2012).
Temperatur udara dicatat oleh termometer yang
disimpan dalam kotak berkisi-kisi terbuka.
Diketahui sebagai saringan Stevenson, dipasang
setinggi kira-kira 1,25 m dari permukaan tanah.
Termometer ini perlu terlindungi dari presipitasi
dan cahaya langsung dari matahari
(Wilson 2006).
Suhu menyatakan tingkat (derajat) panas atau
dinginnya suatu zat, sedangkan kalor adalah salah
satu bentuk energi yang berpindah dari suatu benda
ke benda yang lainny karena perbedaan suhu. Suhu
di ukur menggunakan termometer.Suhu seringkali
juga diartikan sebagai energi kinetis rata-rata
9
suatu benda. Satuan untuk suhu adalah derajat suhu
yang umumnya dinyatakan dengan satuan derajat
Celsius (°C) disamping tiga sistem skala lain,
yaitu satuan Fahrenheit (F), satuan Reamur (R),
dan satuan Kelvin (K) (Purwoko 2009)
Suhu seringkali juga diartikan sebagai energi
kinetis rata-rata suatu benda. Satuan untuk suhu
adalah derajat suhu yang umumnya dinyatakan dengan
satuan derajat Celsius (°C) disamping tiga sistem
skala lain, yaitu satuan Fahrenheit (F), satuan
Reamur (R), dan satuan Kelvin (K). Alat yang
digunakan untuk mengukur temperatur dikenal dengan
nama termometer. Berdasarkan prinsip fisikanya,
termometer dapat digolongkan ke dalam empat macam
termometer berdasarkan prinsip pemuaian,
termometer berdasarkan prinsip arus listrik,
thermometer berdasarkan perubahan tekanan dan
volume gas, dan termometer berdasarkan prinsip
perubahan panjang gelombang cahaya yang
dipancarkan oleh suatu permukaan bersuhu tinggi
(Koestoer 2003).
4. Kelembaban Udara
Kelembaban udara adalah bayaknya uap air yang
terkandung dalam udara atau atmosfer. Besarnya
tergantung dari masukknya uap air ke dalam
atmosfer, karena adnay penguapan dari air yang ada
di lautan, danau, dan sungai, maupun dari air
10
tanah. Banyaknya air didalam udara dipengaruhi
oleh ketersediaan air, sumber uap, suhu udara,
tekanan udara, dan angin. Uap air dalam atmosfer
dapat berubah bentuk menjadi cari atau padat yang
akhirnya dapat jatuh ke bumi antara lain sebagai
hujan. Kelembaban udara yang cukup besar memberi
petunjuk langsung bahwa udara banyak mengandung
uap air atau udara dalam keadaan basah (Swarinoto
2011).
Kelembaban udara merupakan uap air (gas) yang
tidak dapat dilihat, yang merupakan salah satu
bagian dari atmosfer. Banyaknya uap air yang
dikandung oleh hawa tergantung pada temperatur.
Makin tinggi temperatur makin banyak uap air yang
dapat dikandung oleh hawa (Soekirno 2010).
Kelembaban udara menggambarkan kandungan uap
air di udara. Kandungan uap air di udara dapat
dinyatakan sebagai kelembaban mutlak, kelembaban
nisbi (relatif) maupun defisit tekanan uap air.
Kelembaban nisbi membandingkan antara tekanan uap
air aktual dengan keadaan jenuhnya pada kapasitas
udara untuk menampung uap air (Jason 2010).
Sebaran kelembaban udara menurut waktu
berkaitan dengan penerimaan radiasi matahari di
bumi sehingga terbentuk pola sebaran kelembaba
udara antara siang dan malam hari. Pada siang hari
energi radiasi matahari cenderung kuat akan
11
meningkatkan suhu udara. Pada kondisi tersebut
bila tekana uap aktual di udara teetap maka
kelembaban relatif udara akan berkurang. Demikian
sebaliknya, pada malam hari pada saat suhu udara
mencapai titik suhu terendah bila bersentuhan
dengan benda yang suhunya lebih rendah dari titik
embun akan terbentuk embun. Sebaran kelembaban
udara menurut waktu, dimana kelemban nisbi menurut
tempat tergantung pada suhu yang menentukan
kapasitas udara untuk menampung uap air aktual di
tempat tersebut. Kandungan uap air aktual di suatu
tempat ditentukan oleh ketersediaan air dan energi
untuk menguapkannya (Hasna 2012)
Kelembaban udara adalah tingkat kebasahan
udara karena dalam udara air selalu terkandung
dalam bentuk uap air. Kandungan uap air dalam
udara hangat lebih banyak daripada kandungan uap
air dalam udara dingin. Kalau udara banyak
mengandung uap air didinginkan maka suhunya turun
dan udara tidak dapat menahan lagi uap air
sebanyak itu. Uap air berubah menjadi titik-titik
air. Udara yan mengandung uap air sebanyak yang
dapat dikandungnya disebut udara jenuh (Kusnadi
2010).
Besaran yang sering dipakai untuk menyatakan
kelembaban udara adalah kelembaban nisbi yang
diukur dengan psikrometer atau higrometer.
12
Kelembaban nisbi berubah sesuai tempat dan waktu.
Pada siang hari kelembaban nisbi berangsur-angsur
turun kemudian pada sore hari sampai menjelang
pagi bertambah besar (BMKG 2009).
5. Curah Hujan
Hujan adalah sebuah presipitasi berwujud
cairan, berbeda dengan presipitasi non-cair
seperti salju, batu es dan slit. Hujan memerlukan
keberadaan lapisan atmosfer tebal agar dapat
menemui suhu di atas titik leleh es di dekat dan
di atas permukaan Bumi. Curah hujan dinyatakan
sebagai tebal lapisan air yang jatuh di atas
permukaan tanah rata seandainya tidak ada
infiltrasi dan evaporasi. Satuannya adalah mm
(Nasir dan Maman 2008).
Kerapatan pemasangan kerapatan hujan pada
suatu wilayah harus memperhatikan hujan dan
kondisi wilayah. Penentuan hujan wilayah yang
berdasrkan pada beberapa penangkar hujan yang
tersebar di wilayah itu akan semakin baik data
yang dihasilkan. Data ini kemudian akan dianalisis
hujan wilayahnya, ada dua metode yang dapat
digunakan yaitu metode poligon theissen dan isohit
(Hidayat 2008).
Kondisi fisiografis wilayah Indonesia dan
sekitarnya, seperti posisi lintang, ketinggian,
pola angin (angin pasat dan monsun), sebaran
13
bentang darat dan perairan, serta pegunungan atau
gunung-gunung yang tinggi berpengaruh terhadap
variasi dan tipe curah hujan di wilayah Indonesia.
Berdasarkan pola umum terjadinya, terdapat 3
(tiga) tipe curah hujan, yakni: tipe ekuatorial,
tipe monsun dan tipe lokal. Tipe ekuatorial proses
terjadinya berhubungan dengan pergerakan zona
konvergensi ke utara dan selatan, dicirikan oleh
dua kali maksimum curah hujan bulanan dalam
setahun, wilayah sebarannya adalah Sumatra dan
Kalimantan. Tipe monsun dipengaruhi oleh angin
laut dalam skala yang sangat luas, tipe hujan ini
dicirikan oleh adanya perbedaan yang jelas antara
periode musim hujan dan kemarau dalam setahun, dan
hanya terjadi satu kali maksimum curah hujan
bulanan dalam setahun, wilayah sebarannya adalah
di pulau Jawa, Bali dan Nusa tenggara. Tipe lokal
dicirikan dengan besarnya pengaruh kondisi
lingkungan fisis setempat, seperti bentang
perairan atau lautan, pegunungan yang tinggi,
serta pemanasan lokal yang intensif, pola ini
hanya terjadi satu kali maksimum curah hujan
bulanan dalam waktu satu tahun, dan terjadi
beberapa bulan kering yang bertepatan dengan
bertiupnya angin Muson Barat, sebarannya meliputi
Papua, Maluku dan sebagian Sulawesi. Jumlah curah
hujan juga dipengaruhi oleh arah datang angin,
14
pada sisi pegunungan atau gunung yang menghadap
arah datang angin lembab (windward side) curah
hujannya tinggi dan pada sisi sebelahnya (leeward
side) curah hujannya sangat rendah atau rendah
(Tukidin 2010).
Hujan merupakan susunan kimia yang cukup
kompleks dan bervariasi dari tempat yang satu ke
tempat yang lain, dari musim ke musim pada tempat
yang sama dan dari waktu hujan yang berbeda. Air
hujan terdiri atas ion-ion natrium, kalium,
kalsium, khlor, bikarbonat, dan sulfat yang
merupakan jumlah yang besar bersama-
sama(Wisnubroto et al 2007).
Pencatat hujan (recording garage) biasanya dibuat
sedemikian rupa, sehingga dapat bekerja secara
otomatis. Dengan alat ini dimungkinkan pencatatan
tinggi hujan setiap saat, sehingga intensitas
hujan pada saat tertentu dapat diketahui pula.
Dipasaran telah terdapat beberapa tipe yang
diproduksi antara lain pencatat jungkit dan
pencatat pelampung
(Soemarto 2008).
6. Angin
Angin adalah gerak udara yang sejajar dengan
permukaan bumi. Udara bergerak dari daerah
bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah.
Angin diberi nama sesuai dengan arah mana angin
15
datang, misalnya angin laut adalah angin yang
bertiup dari laut ke darat (Hanum 2009).
Angin bergerak secara horizontal dan vertikal
dengan kecepatan yang bervariasi dan berfluktuasi
secara dinamis. Faktor pendorong bergeraknya massa
udara adalah perbedaan tekanan udara antara suatu
tempat dengan tempat yang lain. Angin selalu
bergerak dari udara yang memiliki tekanan tinggi
menuju ke tekanan rendah. Rotasi bumi pada
porosnya, akan menimbulkan gaya yang akan
mempengaruhi pergerakan angin. Pengaruh rotasi
bumi terhadap pergerakan angin di sebut dengan
gaya Corriolis yaitu pembelokan arah pergerakan
angin akibat rotasi bumi (Lakitan 2002).
Variasi angin harian hanya berarti di dekat
tanah dan yang paling nyata ialah selama musim
panas. Kecepatan-kecepatan angin permukaan berada
pada suatu minimum sekitar matahari tersebut, dan
naik ke suatu maksimum pada sore hari. Pada kira-
kira 300 meter (1000 ft) di atas tanah, nilai
maksimum terjadi pada malam hari dan minimumnya
pada siang hari (Hermawan 2007).
Kelembaban yang cukup mungkin dapat
menguntungkan. Namun di daerah-daerah kering,
banyak angin berpengaruh sangat buruk, karena
mengakibatkan pengeringan yang kuat. Angin
16
mempunyai pengaruh mekanis, yang kadang-kadang
besar artinya (Vink 2007).
Kecepatan dan arah angin masing-masing diukur
dengan anemometer dan penunjuk arah angin.
Anemometer yang lazim adalah anemometer cawan yang
terbentuk dari lingkaran kecil sebanyak tiga
(kadang-kadang empat) cawan yang berputar
mengitari sumbu tegak. Kecepatan putaran mengukur
kecepatan angin dan jumlah seluruh perputaran
mengitari sumbu itu memberi ukuran berapa jangkau
angin, jarak tempuh kantung tertentu udara dalam
waktu yang ditetapkan
(Foth 2008).
Variasi angin harian hanya berarti di dekat
tanah dan yang paling nyata ialah selama musim
panas. Kecepatan-kecepatan angin permukaan berada
pada suatu minimum sekitar matahari tersebut, dan
naik ke suatu maksimum pada sore hari. Pada kira-
kira 300 meter (1000 ft) di atas tanah, nilai
maksimum terjadi pada malam hari dan minimumnya
pada siang hari (Hermawan 2007).
7. Evapotranspirasi
Evaporasi adalah peristiwa berubahnya air
menjadi uap. Uap ini kemudian bergerak dari
permukaan tanah atau permukaan air ke udara. Suatu
tajuk hutan yang lebat menaungi permukaan di
bawahnya dari pengaruh radiasi matahari dan angin
17
yang secara drastis akan mengurangi evaporasi pada
tingkat yang lebih rendah (Sudarsono 2007).
Penguapan adalah proses perubahan air dari
bentuk cair menjadi bentuk gas (uap). Ada dua
macam penguapan, yaitu evaporasi (penguapan air
secara langsung dari lautan, danau, sungai) dan
transpirasi (penguapan air dari tumbuh-tumbuhan
dan lain-lain, makhluk hidup). Gabungan antara
evaporasi dan transpirasi disebut evapotranspirasi
(Wuryanto 2000).
Evaporasi adalah peristiwa berubahnya air
menjadi uap. Uap ini kemudian bergerak dari
permukaan tanah atau permukaan air ke udara.
Evaporasi merupakan penguapan yang terjadi pada
permukaan tanah. Evaporimeter yang digunakan pada
praktikum kali ini adalah evaporimeter yang
menggunakan bejana penguapan berupa panic atau
tanki yang berisi air bersih (Runtunuwu et al
2008).
Evaporasi dilaksanakan dengan cara menguapkan
sebagian dari pelarut pada titik didihnya,
sehingga diperoleh larutan zat cair pekat yang
konsentrasinya lebih tinggi. Uap yang terbentuk
pada evaporasi biasanya hanya terdiri dari satu
komponen, dan jika uapnya berupa campuran umumnya
tidak diadakan usaha untuk memisahkan komponen
komponennya. Dalam evaporasi zat cair pekat
18
merupakan produk yang dipentingkan, sedangkan
uapnya biasanya dikondensasikan dan dibuang.
Disinilah letak perbedaan antara evaporasi dan
distilasi (Ade 2010).
Evapotranspirasi adalah kombinasi dari dua
proses yaitu proses kehilangan air pada permukaan
tanah disebut evaporasi dan proses kehilangan air
dari tanaman. Selama air tersedia,
evapotranspirasi akan berlangsung pada laju
maksimum yang mungkin dan hanya tergantung pada
jumlah energi yang tersedia. Evaporasi dipengaruhi
oleh faktor meteorologi, termasuk didalamnya
radiasi surya, suhu permukaan evaporasi, selisih
tekanan uap, kecepatan angin dan turbulensi udara.
Radiasi surya merupakan sumber energi utama.
Evapotranspirasi dikendalikan oleh tiga kondisi,
yaitu kapasitas udara untuk menampung lebih banyak
uap air, jumlah energi yang tersedia dan digunakan
dalam proses evaporasi dan transpirasi sebagai
bahan laten, dan derajat turbulensi atmosfer
bagian bawah yang dibutuhkan untuk memindahkan
lapisan udara yang telah jenuh dengan uap air
dekat permukaan dan menggantinya dengan udara yang
belum jenuh. Tidak semua presipitasi yang mencapai
permukaan secara langsung berinfiltrasi kedalam
tanah atau melimpas di atas permukaan tanah.
Sebagian darinya, secara langsung atau setelah
19
penyimpanan permukaan , hilang dalam bentuk
evaporasi, yaitu proses dimana air menjadi uap
(Allen et al 2000).
Evapotranspirasi (ET) adalah ukuran total
kehilangan air (penggunaan air) untuk suatu luasan
lahan melalui evaporasi dari permukaan tanaman.
Secara potensial ET ditentukan hanya oleh unsur –
unsur iklim. Sedangkan secara aktual ET juga
ditentukan oleh kondisi tanah dan sifat tanaman
(Handoko 2008).
8. Awan
Awan adalah kumpulan butir butir air, kristal
es atau gabungan antara keduanya yang masih
melekat pada inti-inti kondensasi, yang melayang
di atmosfer.Bentuk awan di bagi 4 kelompok utama
yaitu awan tinggi, awan sedang, awan rendah dan
awan vertikal. Awan tinggi, dengan ketinggian 6-12
km jenis awannya sirus, sirokumulus dan
sirostratus. Awan sedang dengan ketinggian 2-6 km
jenis awannya altokumulus dan altostratus. Awan
rendah dengan ketinggian 0.8-2 km, jenis awannya
yaitu stratokumulus, stratus, nimbostratus. Awan
vertikal ketinggian kurang dari 2 km yaitu awan
kumulus dan kumulonimbus (Samadi 2010).
Awan merupakan kumpulan dari titik-titik air
yang demikian banyak jumlahnya dan terletak pada
titik kondensasi serta melayang-layang tinggi di
20
udara. Tiap-tiap macam awan mempunyai sifat
sendiri-sendiri mengenai kelembaban dan suhunya.
Untuk terjadinya hujan perlu adanya awan-awan
cumulus, sedangkan awan cumulonimbus mengakibatkan
hujan besar (Kartasapoetra 2008).
Adanya awan di atmosfer akan menyebabkan
berkurangnya radiasi matahari yang diterima di
permukaan bumi. Karena radiasi yang mengenai awan
oleh uap air yang ada di dalam awan akan
dipancarkan, dipantulkan, dan diserap, maka dari
tiu awan sangat berguna bagi kehidupan, agar sinar
matahari yang datang ke bumi tidak terlalu panas
(BMKG 2009).
Di daerah tropis awan maksimum pada musim
panas dan sesuai dengan curah hujan maksimum. Di
daerah pantai barat subtropik awan dan curah hujan
maksimum pada musim dingin. Di daerah pedalaman
benua variasi awan tahunan berlawanan dengan curah
hujan tahunan. Pada musim panas curah hujan
maksimum, tetapi awan minimum karena pada musim
panas awan cumulus yang bersifat lokal, sedang
pada musim dingin awan strato meliputi daerah yang
luas. Awan merupakan kumpulan dari titik –titik
air yang demikian banyak jumlahnya dan terletak
pada titik kondensasi serta melayang-layang tinggi
di udara. Awan terbagi menjadi empat macam yaitu
tinggi (pada ketinggian 7 Km dari permukaan laut,
21
contoh Cirrus), pertengahan (pada ketinggian 2-7
Km, contoh Altostratus), rendah (pada ketinggian
kurang dari 2 Km, contoh Stratocumulus),
berkembang vertikal (pada ketinggian pada 1-20 Km,
contoh Cumulus) (Sugiman dan Masri 2006).
Awan merupakan penghalang pancaran sinar
matahari ke bumi. Jika suatu daerah terjadi awan
(mendung) maka panas yang diterima bumi relatif
sedikit, hal ini disebabkan sinar matahari
tertutup oleh awan dan kemampuan awan menyerap
panas matahari. Permukaan daratan lebih cepat
menerima panas dan cepat pula melepaskan panas,
sedangkan permukaan lautan lebih lambat menerima
panas dan lambat pula melepaskan panas sehingga
apabila udara pada siang hari diselimuti oleh
awan, maka temperatur udara pada malam hari akan
semakin dingin (Ahmadi 2010).
C. HASIL PENGAMATAN
1. Radiasi Surya
Gambar 1.1 Sunshine Recorder tipe Cambell Stokesa. Bagian-bagian utama
1) Lensa bola pejal.
1
23
45
22
2) Busur pemegang bola kaca pejal.
3) Kertas pias
4) Mangkuk tempat kertas pias.
5) Sekrup pengatur kemiringan.
b. Prinsip Kerja
1)Memasang kertas pias pada alat sunshine
recorder. Kertas pias akan terbakar jika ada
sinar matahari yang jatuh ke bola kaca. Bola
kaca ini berfungsi memfokuskan sinar yang
jatuh di atasnya sehingga dapat membakar
kertas pias yang berada di bawahnya.
2)Menghitung presentasi kertas pias yang
terbakar.
3)Menggambar kertas pias yang telah digunakan.
4)Menentukan lama penyinaran matahari dalam
satu hari pengamatan.
2. Tekanan Udara
Gambar 1.2 Barometer
a. Bagian-bagian utama
1) Jarum penunjuk
2) Skala
3) Sangkar
1
2
3
23
b. Prinsip Kerja
1) Membaca angka yang berada pada barometer,
Jarum akan menunjukkan angka yang
mengindikasikan tekanan udara di daerah
tersebut. Angka yang dibaca adalah angka
yang berada pada di baris kedua dari
pinggir, yang paling dalam (berwarna merah).
2) Melakukan pengamatan tiap 20 menit sekali
dan merekap untuk satu hari pengamatan.
24
3. Suhu Udara dan suhu Tanah
Gambar 1.3 Thermometer maximum dan minimum
a. Bagian-bagian utama
1) Termometer Maksimum
2) Termometer Minimum
3) Statif
4) Dasar statif
5) Termometer bola kering
6) Termometer bola basah
b. Prinsip kerja
1) Untuk mengetahui Suhu udara terendah dalam
suatu periode tertentu (Termometer Minimum)
dapat diketahui dengan membaca angka pada
skala bertepatan dengan ujung kanan
penunjuk.
2) Untuk mengetahui Suhu udara tertinggi dalam
suatu periode tertentu (Termometer Maximum)
3
1
2
4
56
25
dapat diketahui dengan membaca angka pada
skala yang bertepatan dengan air raksa.
Gambar 1.3.2 Thermometer maximum dan minimum tipe
six
a. Bagian-bagian Utama
1) Termometer Maksimum
2) Termomeer Minimum
b. Prinsip kerja
1) Suhu tertinggi pada termometer maksimum
dapat diketahui dengan membaca angka pada
skala yang bertepatan dengan air raksa.
2) Suhu terendah pada termometer minimum dapat
diketahui dengan membaca angka yang
bertepatan dengan ujung kanan penunjuk.
Gambar 1.3.3 Thermometer Tanah Bengkok
1
1
3 4 5 6
2
2
26
a. Bagian-bagian utama
1) Termometer tanah 0 cm
2) Termometer tanah 2 cm
3) Termometer tanah 5 cm
4) Termometer tanah 10 cm
5) Termometer tanah 50 cm
6) Termometer tanah 100 cm
7) Air raksa
8) Skala penunjuk
b. Prinsip kerja
1) Mengguanakan termometer tanah yang
prinsipnya sama dengan termometer hanya
dengan pipa kapiler yang lebih panjang dari
thermometer air raksa, sesuai dengan
kedalaman tanah yang akan du ukur suhunya.
2) Jarak antara reservoir dengan skala terendah
lebih panjang untuk mempermudah pembacaan.
3) Besarnya suhu tanah tiap kedalaman sama
seperti yang tercantum dalam termometer.
27
4. Kelembaban Udara
Gambar 1.4 Termohigrograf
a. Bagian-bagian Utama
1) Lempeng bimetal
2) Rambut
3) Sistem tuas higrograf
4) Sistem tuas termohigrograf
5) Silinder kertas grafik
6) Tabung higrograf
7) Tangkai petunjuk kelembaban udara
8) Tabung termohigrograf
b. Prinsip Kerja
1) Mambaca skala pada kertas grafik membaca
skala pada termohigrograf. Skala pada bagian
atas untuk kelembaban udara dan skala bagian
bawah untuk suhu udara.
1
372
4 6
8
5
28
5. Curah Hujan
Gambar 1.5.1 Ombrometer
a. Bagian-bagian Utama
1) Mulut penakar seluas 100 cm²
2) Corong ombrometer
3) Tabung penampung denga kapasitas curah hujan
300-500 mm
4) Kran untuk mengeluarkan air hujan tertampung
5) Gelas ukur
b. Prinsip Kerja
1) Curah hujan yang jatuh pada corong mengalir
ke tabung penampung sehingga permukaan air
naik.
2) Membuka kran yang ada kemudian menggunakan
gelas ukur sebagai penampung, dan mengukur
seberapa air yang ada.
3
1
4
2
29
Gambar 1.5.2 Ombrograf
a. Bagian-bagian utama
1) Ombrometer
2) Tabung penampung air
3) Skala petunjuk intensitas curah hujan
4) Pena petunjuk skala
5) Kertas pias
6) Pelampung
7) Drum
b. Prinsip kerja
1) Air hujan yang masuk ke dalam ombrograf
melalui corong
2) Curah hujan yang jatuh pada corong mengalir
ke tabung penampung sehingga permukaan air
naik dan mendorong pelampung dimana
sumbunya bertepatan dengan sumbu pena.
3) Pena bergerak naik turun untuk
menggambarkan grafik curah hujan pada
kertas pias. , bergeraknya kertas searah
1
4
3
2
30
putaran jam dan sesuai dengan waktu yang
ada.
4) Air hujan akan kembali keluar dari ombograf
dengan melalui celah.
6. Angin
Gambar 1.6.1 Wind vane
a. Bagian-bagian Utama
1) Batang petunjuk arah mata angin
2) Baling-baling
3) Papan
4) Empat arah mata angin
b. Prinsip Kerja
1) Angin yang berhembus akan membentur
penangkap angin sehingga akan menggerakkan
panah arah mata angin.
2) Ujung panah merupakan posisi asal dari angin
tersebut berhembus.
1
32
4
1
4
31
Gambar 1.6.2 Anemometer
a. Bagian-bagian utama
1) Tiga buah mangkok sebagai baling-baling
yang dibatasi sudut 120oPoros berputar
2) Penunjuk kecepatan angin
3) Tiang
b. Prinsip kerja
1) Angin akan mendorong ketiga corong tersebut
untuk berputar.
2) Dengan ketiga corong tersebut berputar
dapat digunakan sebagai acuan untuk melihat
seberapa besar kecepatan angin.
7. Evaporasi
Gambar 1.7 Panci Evapotranspirasi
a. Bagian-bagian Utama
1) Panci
2
4
1
2
3
32
2) Still well cylinder
3) Kayu
4) Termometer
b. Prinsip Kerja
1) Pengukuran dilakukan pada permukaan air
dalam keadaan tenang didalam tabung peredam
riak (Still Well Cylinder) berbentuk silinder untuk
mencegah terjadinya gelombang air pada ujung
jarum yang digunakan untuk mengukur tinggi
permukaan air pada panci evaporimeter.
2) Batang pancing ini terletak menggantung
ditabung peredam riak sebagai petunjuk
tinggi permukaan air.
8. Awan
Gambar 1.8 Awan
a. Bagian-bagian Utama
1) Awan tebal dengan gerakan vertikal di bagian
atas
2) Berbentuk seperti bulu domba
b. Prinsip Kerja
33
1) Mengarahkan pandangan ke langit, bagi
menjadi 4 kuadran
2) Mengamati awan beserta ciri-cirinya pada
setiap kuadran, tentukan awan yang dominan
kemudian memberikan nama sesuai dengan
famili awan tersebut dan ketinggiannya.
3) Menggambar bentuk awan yang ada setiap 1 jam
sekali.
D. Pembahasan
a. Radiasi Surya
Pengamatan unsur cuaca radiasi surya ini
dilakukan di Desa Sukosari, Kecamatan Jumantono,
Kabupaten Karanganyar. Pengamatan radiasi surya
meliputi lama penyinaran dan intensitas radiasi.
Lama penyinaran adalah lamanya permukaan bumi
mendapat penyinaran dari matahari dalam satu
hari. Satuan lama penyinaran adalah jam/hari.
Alat yang digunakan untuk mengetahui/mengukur
lamanya penyinaran dalam satu hari adalah Sunshine
Recorder.
Selain itu dapat juga menggunakan alat
Sunshine Recorder tipe Cambell Stokes. Pada sunshine
recorder ini, kertas pias akan terbakar karena
sinar matahari yang difokuskan oleh bola kaca
pada alat ini. Semakin besar intensitas
penyinaran, maka kertas pias akan banyak yang
34
terbakar. Pada pengamatan, nampak bahwa kertas
pias tidak terbakar seluruhnya. Faktor – faktor
yang mempengaruhi radiasi surya adalah jarak bumi
ke matahari, konstanta matahari, sudut datng
sinar matahari, lamanya penyinaran, dan keadaan
atmosfer.
Intensitas cahaya matahari sangat
mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan
tanaman. Lama penyinaran juga sangat mempengaruhi
proses pertumbuhan tanaman, terutama pada proses
fotosintesis. Dengan mengamati pola penyinaran
cahaya matahari pada suatu tanaman dapat
dikembangkan dan digunakan dalam pengambilan pola
kebijakan budidaya tanaman, dan dapat mengetahui
tindakan antisipasi apabila terjadi perubahan
lama penyinaran yang tiba-tiba dan ekstrim.
Sehingga, semakin kita meneliti pengaruh cahaya
matahari terhadap tanaman dapat membuat kita
lebih mengetahui tanaman apa yang sesuai dengan
intensitas cahaya matahari yang rendah dan mana
yang cocok dengan intensitas cahaya matahari yang
tinggi.
b. Tekanan Udara
Alat yang digunakan untuk mengukur tekanan
udara disebut barometer. Tinggi angka yang
ditunjukkan oleh barometer selain ditunjukkan
oleh tekanan udara pada saat itu, juga
35
dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain
seperti: altitute (tinggi tempat), latitude
(letak lintang) dan gravitasi, serta suhu udara.
Hal ini disebabkan karena gradien tekanan udara
vertikal yang tidak selalu tetap karena kerapatan
udara dipengaruhi oleh faktor-faktor: suhu, kadar
uap air di udara dan gravitasi.
Pengaruh letak lintang terhadap tekanan udara
yaitu akibat adanya gaya gravitasi yang terkecil
di khatulistiwa dan terbesar di kutub yang
menyebabkan tekanan udara di sekitar khatulistiwa
cenderung lebih tinggi dibandingkan di daerah
kutub. Kemudian pengaruh suhu atau temperatur
dalam pengukuran tekanan udara adalah apabila
suhunya naik, air raksa akan mengembang dan jika
suhunya turun air raksa cenderung menyusut,
karena itu pengukuran tekanan udara di daerah
tropis cenderung lebih tinggi.
Tekanan udara akan berpengaruh terhadap
pertumbuhan tanaman, misal pada saat pembungaan
terjadi. Tekanan udara yang tinggi akan dapat
mengugurkan bunga-bunga sehingga pembuahan tidak
akan terjadi. Hal ini akan merugikan hasil panen
terutama bagi petani buah-buahan.Tekanan udara
yang tinggi akan menggugurkan bunga-bunga
sehingga pembuahan tidak akan terjadi. Hal ini
36
sangat merugikan hasil panen, terutama bagi
petani buah-buahan.
c. Suhu Udara
Suhu merupakan derajat panas atau dingin
suatu benda atau dapat dinyatakan sebagai energi
kinetis rata-rata suatu benda. Alat yang
digunakan untuk mengukur suhu disebut termometer
yang dalam satuan Celcius (0C), Reamur (0R),
Fahrenheit (0F) dan Kelvin (0K).Alat yang
digunakan untuk mengukur suhu tanah dan suhu
udara adalah termometer tanah bengkok dan
termometer maximum dan minimum. Perubahan suhu
tanah akan menaikan air raksa menunjukkan suhu
tanah pada skala tertentu.
Suhu tanah merupakan derajat panas atau
dingin pada tanah baik pada permukaan tanah
maupun pada berbagai macam kedalaman tanah yang
berbeda. Suhu tanah berkaitan dengan pertumbuhan
tanaman karena dapat mempengaruhi keaadan
perakaran dari tanaman.Suhu tanah diukur dengan
termometer biasa hanya saja dibenamkan ke dalam
tanah dengan beragam kedalaman. Pada tiap
kedalaman didapatkan nilai temperatur yang
berbeda-beda. Semakin dangkal (dekat permukaan
tanah) maka suhunya makin tinggi, sebaliknya
makin dalam (jauh dari permukaan tanah) maka
temperaturnya makin rendah. Keadaan ini dapat
37
terjadi dimungkinkan karena adanya pengaruh
cahaya matahari. Semakin dangkal maka mendapat
radiasi lebih besar dan semakin dalam radiasi
surya makin kecil yang ikut mempengaruhi
temperatur tanah. Tanah lapisan atas yang lebih
gelap juga lebih mampu menyerap sinar matahari
lebih banyak dari pada lapisan bawah sehingga
juga lebih panas.
Suhu yang diukur dalam praktikum ini adalah
suhu udara dan suhu tanah. Masing-masing suhu ini
berpengaruh terhadap besarnya vegetasi tanaman.
Suhu udara pada sangkar 1 pengukurannya dengan
menggunakan termometer bola basah dan bola
kering.
Suhu rata-rata harian terendah terjadi di
pagi hari dan tertinggi (maksimum) setelah siang
hari. Naik turunnya suhu udara dalam waktu satu
hari disebut siklus harian. Siklus tersebut
akibat dari perbandingan antara matahari dengan
radiasi bumi yang diradiasikan ke atmosfer setiap
saat dalam waktu satu hari.
Suhu tanah sangat berperan penting bagi
kelangsungan hidup tumbuhan oleh aktifitas
perakaran. Pengukuran pada praktikum kali ini
dilakukan pada kedalaman 0 cm, 2 cm, 5 cm, 10 cm,
50 cm dan 100 cm. Suhu tanah rata-rata pada
kedalaman 0 cm, 2 cm, 5 cm, 10 cm,50 cm dan 100
38
cm berturut-turut adalah 35.8, 37.2, 32, 35, 30
dan 31. Semakin besar kedalamannya maka suhunya
semakin kecil. Pengaruh suhu tanah pada tanaman
yaitu pada perkecambahan biji, pada aktivitas
mikroorganisme dan perkembangan penyakit tanaman.
Faktor pengaruh suhu tanah yaitu faktor eksternal
(radiasi matahari, keawanan, curah hujan, angin
dan kelembaban udara) dan internal (tekstur
tanah, struktur dan kadar air tanah, kandungan
bahan organik dan warna tanah).
Faktor-faktor yang mempengaruhi suhu di
permukaan bumi ialah pengaruh ketinggian tempat,
jumlah radiasi yang diterima, pengaruh daratan
atau lautan, pengaruh angin secara tidak
langsung. Misalnya angin yang membawa panas dari
sumbernya secara horizontal, tutupan, dan tipe
tanah. Ada juga angin yang membawa dingin.
d. Kelembaban Udara
Kelembaban udara ini diukur menggunakan alat
yang bernama termohigograf. Suhu udara dan
kelembaban udara dapat langsung dibaca pada
kertas grafik yang dipasang pada alat tersebut.
Skala bagian atas untuk suhu udara dan skala
bagian bawah menunjukkan kelembaban udara.
Dalam bidang pertanian kelembaban yang besar
berpengaruh pada kondisi tanaman. Jika kelembaban
tinggi maka jamur dan penyulut tumbuh-tumbuhan
39
akan menjadi subur yang dapat menyerang tanaman,
serta akan mengakibatkan hasil sayuran dan buah-
buahan cepat membusuk. Udara lembab akan
berakibat menghambat transpirasi sehingga
mengurangi laju perpindahan larutan zat hara dari
tanah ke organ tanaman. Pada umumnya kelembaban
berlawanan dengan suhu, kelembaban maksimum pada
pagi hari dan minimum pada sore hari secara
harian.
e. Curah Hujan
Alat yang digunakan untuk mengukur curah
hujan adalah ombrograf yang mencatat secara
otomatis dan ombrometer secara manual. Pada
ombrometer besar curah hujan dapat diketahui
dengan mengukur banyaknya air hujan yang telah
tertampung digelas ukur. Prinsip kerja ombrometer
adalah curah hujan yang jatuh pada corong
mengalir ke tabung penampung sehingga permukaan
air naik dan mendorong pelampung dimana sumbunya
bertepatan dengan sumbu pena. Tangkai pena
bertinta akan ikut naik dan memberi berkas garis
pada kertas berskala, bergeraknya kertas searah
denagn putaran jarum jam dan sesuai dengan waktu
yang ada. Sedangkan pada ombrograf hanya dengan
membaca grafik pada kertas untuk mengetahui curah
hujan.
40
Air adalah faktor yang lebih penting dalam
produksi tanaman pangan dibandingakan dengan
faktor lingkungan lainnya. Tanaman pangan
memperoleh persediaan air dari akar, itu sebabnya
pemeliharaan kelembaban tanah merupakan faktor
yang penting dalam pertanian. Jumlah air yang
berlebih dalam tanah akan mengubah berbagai
proses kimia dan biologis yang membatasi jumlah
oksigen dan meningkatkan pembentukan senyawa yang
berbahaya bagi akar tanaman. Curah hujan yang
lebat dapat menggangu pembungaan dan penyerbukan.
Curah hujan memegang peranan pertumbuhan dan
produksi tanaman pangan. Hal ini disebabkan air
sebagai pengangkut unsur hara dari tanah ke akar
dan dilanjutkan ke bagian-bagian lainnya.
Fotosintesis akan menurun jika 30% kandungan air
dalam daun hilang, kemudian proses fotosintesis
akan berhenti jika kehilangan air mencapai
60%.Curah hujan adalah jumlah air hujan yang
jatuh di permukaan tanah selama periode tertentu
yang diukur dalam satuan tinggi di atas permukaan
horizontal apabila tidak terjadi penghilangan
oleh proses evaporasi pengaliran dan peresapan
dinyatakan sebagai tebal lapisan air yang ada di
atas permukaan tanah rata seandainya tidak ada
infiltrasi dan evaporasi, dengan satuan
milimeter. Curah hujan 1 mm berarti banyaknya
41
hujan yang jatuh di atas sebidang tanah seluas 1
m2 = 1mm x 1m2 = 0,01 dm x 100 dm2 = 1 dm3 = 1
liter. Hari hujan adalah suatu hari dimana
terkumpul curah hujan 0,5 mm atau lebih.
f. Angin
Alat yang digunakan untuk mengamati ada dua.
Pertama ada alat untuk mengamati arah angin yaitu
wind vane. Sementara yang kedua adalah untuk
mengukur kecepatan daripada angin itu yaitu
dengan menggunakan alat anemometer. Pada
anemometer ini terdapat tiga mangkok yang
menghadap ke satu jurusan dan akan berputar bila
tertiup angin. Pada p oros putara dipasang alat
pengukur kecepatan yang dapat menunjukkan angka.
Selisih angka pengamatan pertama dengan
pengamatan kedua dibagi jangka waktu pengamatan
merupakan angka rata-rata kecepatan angin dalam
waktu tertentu.
Arah angin mengacu pada dari manakah angin
itu bertiup dan dinyatakan dengan sudut kompas
atau sebutan nama penjuru angin. Sudut 0o atau
360o menunjukkan arah utara, 90o menunjukkan
timur, 180o arah selatan dan 270o arah barat.
Pembagian arah angin selanjutnya dengan sebutan
arah timur laut, tenggara, barat daya dan barat
laut. Untuk menentukkan arah angin pada praktikum
kali ini menggunakan alat penunjuk angin yang
42
disebut Wind Vane. Posisi vane yang menunjukkan
arah angin pada waktu itu.
Angin secara tidak langsung mempunyai efek
penting pada produksi tanaman pangan. Energi
angin merupakan perantara dalam penyebaran tepung
sari pada penyerbukan alamiah, tetapi angin juda
dapat menyebarkan benih rumput liar dan melakukan
penyerbuka silang yang tidak diinginkan. Angin
yang terlalu kencang juga akan menggangu
penyerbukan oleh serangga.
Angin dapat membantu dalam menyediakan karbon
dioksida yang membantu pertumbuhan tanaman,
selain itu juga mempengaruhi suhu dan kelembaban
tanah. Namun pada saat musim kemarau di beberapa
daerah di Indonesia bertiup angan fohn yang dapat
merusak karena bersifat kering dan panas. Pada
siang hari didaerah sekitar pantai, angin laut
dapat menyebabkan masalah karena angin ini
membawa butiran garam yang dapat merusak daun.
g. Evapotranspirasi
Alat yang digunakan untuk mengukur evaporasi
adalah evaporimeter. Evaporimeter yang digunakan
pada praktikum kali ini adalah evaporimeter yang
menggunakan bejana pemguapan berupa panci atau
tangki yang berisi air bersih. Dinding bejana
berwarna putih atau putih metalik, hal ini
ditunjukkan untuk mengurangi pengaruh radiasi.
43
Bantalan kayu yang di gunakan sebagai alas panci
evaporimeter di gunakan untuk menghilangkan
pengaruh suhu tanah terhadap panci evaporimeter
karena balok kayu bersifat isolator sehingga
tidak dapat menghantarkan panas.
Evaporasi adalah penguapan air dari permukaan
bumi ke atmosfer. Proses evapotranspirasi sangat
penting dalam siklus hidrologi dan CWR (Crop Water
Requirement = banyaknya air yang dibutuhkan
tanaman untuk tumbuh). Pada pengamtan kali ini
untuk mengamati besarnya evaporasi, menggunakan
panci evaporimeter. Berbentuk silinder terbuka
dengan lapisan berwarna perak untuk memantulkan
cahaya dan berisi air sebagai indicator
terjadinya evaporasi pada daerah tersebut.
Nilai evaporasi merupakan selisih tinggi
permukaan dari dua kali pengukuran setelah nilai
curah hujan diperhitungkan apabila pada waktu
pengukuran terjadi hujan. Sehingga secara tidak
langsung evaporimeter berhubungan dengan
ombrometer. Perhitungan evaporasi (Eo) :
a. Bila tidak terjadi hujan
Eo = (P0-P1) mm
b. Bila terjadi hujan
Eo = (P0-P1) + x mm
c. Bila hujan sangat lebat sehingga panci terisi
air sampai tumpah atau meluap maka pengukuran
44
penguapan tidak dapat dilakukan dan diberi
tanda ’x’ pada angka pencatatan.
Keterangan :
Eo : Evaporasi
P0 : tinggi permukaan air di awal periode
P1 : tinggi permukaan air di akhir periode
X : besarnya curah hujan
Pengukuran dilakukan pada permukaan air dalam
keadaan tenang didalam tabung peredam riak (Still
Well Cylinder). Still Well Cylinder merupakan silinder
untuk mencegah terjadinya gelombang air pada
ujung jarum atau batang pancing pengukur
micrometer yang digunakan untuk mengukur tinggi
permukaan air pada panci evaporimeter. Keuntungan
penggunaan batang pancing berskala (mikrometer)
ini adalah pengukuran dapat dilakukan lebih cepat
dan mudah, dapat digeser turun atau naik dengan
memutar sekrupnya. Batang pancing pengukur ini
terletak menggantung ditabung peredam riak.
Sebagai penunjuk tinggi permukaan air adalah
ujung pancing yang dibuat runcing. Kelemahannya
terkadang pengamat tidak mengembalikan tinggi
permukaan air dengan cermat sesuai ketentuannya
sehingga proses penguapan berlangsung pada volume
air yang tidak tetap.
Evapotranspirasi ini terjadi bila ada energi
dari matahari yang diperlukan untuk mengubah air
45
dari fase cair menjadi gas dan adanya difusi
setelah uap air terbentuk yang disertai dengan
proses perpindahan atau pengangkutan dari
permukaan yang berevaporasi ke atmosfer sehingga
diperlukan bantuan angin (turbulensi). Faktor
yang mempengaruhi evapotranspirasi antara lain:
suhu udara, angin, tekanan uap ke atmosfer,
kualitas air dan sifat serta bentuk permukaan.
Meningkatnya suhu udara maka energi kinetik
molekul airnya bertambah sehingga lepas dari
permukaan air, dengan kecepatan angin yang tinggi
maka laju evapotranspirasinya bertambah sampai
batas tertentu. Tekanan uap air ke atmosfer yang
rendah mengakibatkan proses evapotranspirasi
lebih cepat. Evapotranspirasi penting sebagai
unsur dari siklus hidrologi dan sebagai penyedia
air yang dapat mencukupi tubuh tumbuhan sepanjang
waktu.
h. Awan
Awan adalah gumpalan uap air yang terapung di
atmosfer. Berdasarkan hasil pengamatan diketahui
bahwa jenis awan pada hari tersebut yaitu strato
cumulus pada ketinggian tertentu. Dan warnanya
putih dan putih abu-abu. Awan mempengaruhi nilai
intensitas radiasi surya karena dengan adanya
awan menghalangi pancaran sinar ke bumi.
Klasifikasi awan adalah sebagai berikut:
46
a. Famili awan tinggi: cirrus, cirro cumulus, dan
cirrostratus
b. Famili awan sedang: altocumulus dan
altostratus
c. Famili awan rendah: stratus, nimbo stratus dan
stratocumulus
d. Famili awan tumbuh vertical: cumulus; cumulus
nimbus dan nimbo stratus
Awan merupakan kumpulan uap air dari proses
penguapan dari bumi dan tanaman. Dalam Siklus
hidrologi, awan memegang peranan penting untuk
menampung uap air. Kesimpulannya awan berperan
penting dalam putaran air di bumi yang
dimanfaatkan oleh manusia.
Siklus hidrologi merupakan siklus air yang
paling tua terbentuk di muka bumi, bahkan
merupakan siklus yangpertama terbentuk di bumi.
Air laut, danau, sungai yang terdapat dipermukaan
bumi menguap (evaporasi) karena panas matahari,
termasuk juga air yang terdapat dalam tumbuhan
(transpirasi), hewan dan manusia (respirasi) juga
mengalami penguapan. Selanjutnya uap tersebut
masuk dalam atmosfera menjadi awan. Awan
mengalami kondensasi, sehingga terjadilah titik
air hujan (presipitasi) dan dengan garfitasi bumi
titik air jatuhke bumi baik di daratan maupun di
lautan. Air hujan yang jatuh di daratan sebagian
47
masuk ke dalam tanah (infiltrasi) dan mengalami
perasapan ke dalam tanah (perkolasi) menjadi air
tanah, sebagain lagi mengalir dipermukaan tanah
(runoff). Air tanah maupun air permukaan mengalir
mengikuti grafitasi bumi menuju daratanyang lebih
rendah, baik melalui air bawah tanah maupun
sungai-sungai. Dalam perjalanannya menuju laut
ataudaerah yang paling rendah, air mengalami
penguapan termasuk laut, sungai, danau, sehingga
siklus hidrologi kembali terjadi, demikian
seterusnya tanpa henti.
Menurut pengamatatn awan yang dilakukan oleh
kelompok kami (kelompok 30) yang kami ambil di
tempat praktikum agroklimatalogi yaitu di
Jumantono termasuk ke dalam tipe awan
Cumulonimbus karena yang kami lihat dengan mata
telanjang, karena awannya besar, padat dan
meluar, puncaknya menyerupai gunung dan menara
yang besar atau seperti cengger ayamdengan warna
yang gelap.
48
E. KOMPREHENSIF
Radiasi surya dipengaruhi jarak bumi dari
surya, intensitas radiasi surya dan jumlah hari.
Radiasi matahari yang diterima oleh bumi kita
(energi matahari) akan diterima dengan cara diserap
oleh aerosol dan awan di atmosfer bumi yang akhirnya
menjadi panas, ditangkis oleh atmosfer (gas-gas dan
aerosol-aerosol), dalam hal ini radiasi ditangkis
dan disebarkan ke segala penjuru, radiasi yang tidak
tertangkis maupun terserap oleh atmosfer, sampai ke
permukaan bumi,dan radiasi yang sampai ke permukaan
bumi yang tidak direfleksi, akan diserap oleh bumi.
Makin tinggi matahari sinar yang diterima makin
banyak sehingga semakin siang, kertas pias yang
terbakar semakin panjang. Hari makin panjang maka
radiasi matahari juga semakin banyak. Kondisi awan
juga mempengaruhi sinar matahari yang sampai ke
bumi. Bila tidak berawan maka sinar matahari yang
sampai ke bumi kurang lebih 66%, bila berawan kurang
lebih 17% dan berawan tipis 48%. Pada saat
pengamatan kondisi awan mayoritas berawan dan agak
tebal karena itu intensitas matahari besarnya 0 %
dalam 1 hari sehingga kertas pias yang terbakar juga
pendek. Dengan intensitas radiasi yang kecil maka
panas matahari hampir tidak ada yang sampai ke bumi
sehingga tanaman kekurangan cahaya matahari dan
tidak dapat melakukan fotosintesis.
49
Tekanan udara suatu wilayah, dipengaruhi
ketinggian wilayah tersebut. Makin tinggi suatu
tempat maka tekanannya semakin rendah. Hal ini
disebabkan karena kerapatannya rendah dan kolom
udara yang makin pendek. Kelembaban relatif di suatu
tempat dipengaruhi oleh kondisi suhu udara dan
kandungan uap air aktual yang ditentukan oleh
ketersediaan air di tempat tersebut. Umumnya
distribusi kelembaban tinggi di pusat-pusat tekanan
rendah. Makin rendah suhu udara makin besar
kapasitas udara menampung uap air, sehingga suhu
siang hari lebih tinggi daripada suhu malam hari,
maka berdampak pada distribusi kelembaban siang hari
yang lebih kecil dibanding malam hari.
Cuaca dan iklim merupakan dua kondisi yang
hampir sama tetapi berbeda pengertian khususnya
terhadap kurun waktu. Cuaca merupakan bentuk awal
yang dihubungkan dengan penafsiran dan pengertian
akan kondisi fisik udara sesaat pada suatu lokasi
dan suatu waktu. Iklim merupakan kondisi lanjutan
dan merupakan kumpulan dari kondisi cuaca yang
kemudian disusun dan dihitung dalam bentuk rata-rata
kondisi cuaca dalam kurun waktu tertentu.
Proses terjadinya cuaca dan iklim merupakan
kombinasi dari variabel-variabel atmosfer yang sama
50
yang disebut unsur-unsur iklim. Unsur-unsur iklim
ini terdiri dari radiasi surya, suhu udara,
kelembaban udara, awan, presipitasi, evaporasi,
tekanan udara dan angin. Unsur-unsur ini berbeda
dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang
disebabkan oleh adanya pengendali-pengendali iklim.
Pengendali iklim atau faktor yang dominan menentukan
perbedaan iklim antara wilayah yang satu dengan
wilayah yang lain adalah posisi relatif terhadap
garis edar matahari (posisi lintang), rotasi dan
revolusi bumi, topografi, gerakan massa regional,
pusat tekanan tinggi dan rendah, keberadaan lautan
atau permukaan airnya termasuk posisi wilayah
terhadap lautan, pola arah angin, rupa permukaan
daratan bumi, dan kerapatan dan jenis vegetasi.
Suhu tanah dipengaruhi oleh radiasi surya,
kondisi awan, curah hujan, suhu udara, angin dan
kelembaban udara. Suhu tanah berbanding lurus dengan
intensitas radiasi, suhu udara, angin dan kelembaban
udara. Temperatur udara terdingin terjadi pada pagi
hari sebelum matahari terbit, kemudian berangsur-
angsur naik seiring besarnya radiasi matahari dan
mengalami penurunan kembali hingga matahari
terbenam. Temperatur akan terus menurun sampai
matahari terbit lagi. Semakin dangkal (dekat
permukaan tanah) maka suhunya makin tinggi karena
mendapatkan radiasi yang lebih besar, sebaliknya
51
makin dalam (jauh dari permukaan tanah) maka
temperaturnya makin rendah. Keadaan ini dapat
terjadi dimungkinkan karena adanya pengaruh cahaya
matahari. Warna tanah lapisan atas yang lebih gelap
juga lebih mampu menyerap sinar matahari lebih
banyak dari pada lapisan bawah sehingga suhu lebih
tinggi. Suhu makin menurun dengan bertambahnya
lintang. Semakin tinggi suhu maka akan menurunkan
derajat kelembaban. Sedangkan suhu udara memberikan
pengaruh terhadap fase reproduksi Suhu udara pada
pagi hari rendah, namun akan bertambah tinggi dengan
adanya penyinaran matahari. Sore hari, suhu udara
akan rendah kembali.
Unsur-unsur iklim juga berpengaruh pada tanaman.
Radiasi surya dan kelembaban udara mempengaruhi
fotosintesis. Laju fotosintesis akan meningkat
seiring dengan meningkatnya intensitas radiasi surya
sampai titik tertentu. Karena pada proses tersebut
terlibat juga reaksi–reaksi biokimia yang melibatkan
enzim, sedangkan enzim bekerja dengan baik pada suhu
yang optimal. Enzim itu sendiri akan rusak apabila
suhu lingkungannya terlalu tinggi. Sedangkan
pengaruh kelembaban udara pada proses fotosintesis
adalah semakin lembab udara maka proses fotosintesis
makin lambat. Angin mempengaruhi transpirasi dan
pemasukan CO2.
52
Cuaca dan iklim muncul setelah berlangsung suatu
proses fisik dan dinamis yang kompleks yang terjadi
di atmosfer bumi. Kompleksitas proses fisik dan
dinamis di atmosfer bumi ini berawal dari perputaran
planet bumi mengelilingi matahari dan perputaran
bumi pada porosnya. Pergerakan planet bumi ini
menyebabkan besarnya energi matahari yang diterima
oleh bumi tidak merata, sehingga secara alamiah ada
usaha pemerataan energi yang berbentuk suatu sistem
peredaran udara, selain itu matahari dalam
memancarkan energi juga bervariasi atau berfluktuasi
dari waktu ke waktu. Perpaduan antara proses-proses
tersebut dengan unsur-unsur iklim dan faktor
pengendali iklim menghantarkan kita pada kenyataan
bahwa kondisi cuaca dan iklim bervariasi dalam hal
jumlah, intensitas dan distribusinya.
Evapotranspirasi dipengaruhi oleh radiasi surya,
suhu, kelembaban, angin dan tekanan udara. Semakin
besar intensitas radiasi surya maka semakin tinggi
suhu dan evapotranspirasi semakin meningkat.
Evapotranspirasi dipengaruhi beberapa faktor.
Semakin besar radiasi surya yang diterima bumi maka
evapotranspirasi semakin besar pula. Besarnya
evapotranspirasi sebanding dengan besarnya suhu
udara, karena itu pada siang hari evapotranspirasi
semakin besar. Kondisi awan yang tipis atau tidak
berawan, evapotranspirasi yang terjadi besar
53
sedangkan makin tebal awan maka evapotranspirasi
yang terjadi makin kecil. Makin cepat angin, maka
penguapan makin cepat. Jika tekanan udara di atas
permukaan air rendah, penguapan menjadi lebih besar.
F. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Dari pengamatan praktikum agroklimatologi dapat
disimpulkan bahwa:
a. Komponen cuaca dan iklim dipengaruhi oleh
radiasi surya, tekanan udara, suhu (suhu udara
dan suhu tanah), ph dan kelembapan, curah
hujan, angin, evapotranspirasi, dan awan.
1) Radiasi surya
Radiasi surya adalah sesuatu yang
menyebar ke arah luar dari suatu sumber,
yang dimana sumber utamanya adalah matahari.
2) Tekanan Udara
Tekanan udara bekerja ke segala jurusan
dan tidak tetap. Jika berada di permukaan
atas maka tekanannya semakin rendah.
3) Suhu (suhu tanah dan suhu udara)
Suhu tanah memberikan pengaruh yang
lebih baik dalam hal pertumbuhan tanaman.
Sedangkan suhu udara memberikan pengaruh
terhadap fase reproduksi.
4) Kelembaban udara
54
Kelembaban adalah konsentrasi uap air di
udara dan dapat diekspresikan dalam
kelembaban absolut, kelembaban spesifik atau
kelembaban relatif.
5) Curah hujan
Curah hujan merupakan jumlah air hujan
yang jatuh di permukaan tanah dimana
bervariasi dari tempat yang satu ke tempat
yang lain, dari musim ke musim pada tempat
yang sama dan dari waktu hujan yang berbeda.
55
6) Angin
Angin merupakan komponen penting dalam
mengatur suhu dan kelembaban udara. Angin
bergerak berdasarkan arah mata angin dan
sudut yang terdapat pada kompas.
7) Evapotranspirasi
Evapotranspirasi adalah proses perubahan
air dari bentuk cair menjadi gas dan
perpindahannya dari suatu permukaan benda
ke atmosfer dan ini terjadi pada tanaman.
8) Awan
Awan merupakan gambaran nyata proses
fisika yang terjadi di atmosfer yang
dimana menjadi indikator kondisi cuaca
yaitu sumber presipitasi dan pengendali
neraca panas.
b. Alat-alat yang digunakan untuk mengukur
unsur-unsur cuaca :
1) Sunshine Recorder merupakan alat untuk
mengetahui lamanya penyinaran.
2) Barometer digunakan untuk mengukur
tekanan udara
3) Termometer minimum digunakan untuk
mengetahui suhu terendah dalam suatu
periode.
56
4) Termometer maximum digunakan untuk
mengetahui suhu tertinggi dalam suatu
periode.
5) Termohigrograf untuk mengetahui
kelembaban udara dan suhu udara
6) Anemometer digunakan untuk mengukur
kecepatan angin
7) Evaporimeter untuk mengetahui besarnya
evapotranspirasi
8) Termometer bola basah dan bola kering
untuk mengetahui kelembaban relative.
9) Termometer tanah bengkok untuk mengukur
suhu tanah.
10) Ombrometer untuk mengetahui curah hujan
secara manual.
11) Ombrogarf untuk mengetahui curah hujan
secara otomatis.
12) Wind vane untuk mengetahui arah angin.
2. Saran
Saran dalam praktikum agroklimatologi
khususnya pada praktikum acara pengamatan
unsur-unsur cuaca diharapkan para praktikan
mampu mengetahui unsur cuaca dan mengetahui
macam alat pengukur tiap unsur tersebut beserta
cara pengunaanya.Untuk proses berjalannya
praktikum agroklimatologi acar pengamatan
57
unsur-unsur cuaca ini diharapkan persediaan
segala alat peralatan dan pendukung praktikum
lebih diperhatikan sehingga pratikum dapat
berjalan dengan lancar. Kerusakan pada alat-
alat mengakibatkan praktikum mengalami ganguan
dan hambatan karena tidak dapat mengetahui cara
penggunaanya.
58
DAFTAR PUSTAKA
Ade, Elbani. 2010. Simulasi Unjuk Kerja Sistem KendaliPID Pada Proses Evaporasi Dengan Sirkulasi Paksa.Jurnal EKHA. Vol 2. Universitas TanjungpuraPontianak.
Ahmadi, Syiham Al. 2010. Faktor-faktor yangMempengaruhi Perbedaan Suhu Udara (Temperatur).http://www.syiham.co.cc diakses pada tanggal 8 November2014.
Allen et al. 2000. Penguapan udaara maksimal pada wilayah dengancurah hujan tinggi. Jurnal Penguapan Udara, Vol. 1, No.2, 2000:125-132. PT Widjaya Karma. Bekasi
BMKG. 2009. http://www.bmkgjateng.com. Diakses padatanggal 8 November 2014. Diakses Hari Minggu pukul16.30
Foth, Henry D. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Tanah edisi ke-7. GadjahMada University Press. Yogyakarta.
Hanum, C. 2009. Penuntun Praktikum Agroklimatologi. ProgramStudi Agronomi, Fakultas Pertanian, UniversitasSumatera Utara, Medan.
Hardjodinomo, S. 2007. Ilmu Iklim dan Pengairan. Binacipta.Bandung.
Hasan, U. 2007. Dasar Meterorologi Pertanian 2. SurunganJakarta.
Hermawan. 2007. Pengaruh Kecepatan Angin dengan KeadaanSekitar. Jurnal Lingkungan 23 (3) : 221-234.
Jason. 2010. Yang Dimaksud Kelembaban Udara. www. Answers.yahoo.com.
Kartasapoetra, A.G. 2008. Klimatologi : Pengaruh iklim TerhadapTanah dan Tanaman Edisi Revisi. Bumi Aksara. Jakarta.
Koesmaryono, Yonny. 2008. Kapita Selekta Agroklimatologi.
Bogor. IPB.
Koestoer, R. A., 2003. Perpindahan Kalor untuk MahasiswaTeknik. Salemba Teknika, Jakarta.
59
Koestoer, R. A., 2003. Perpindahan Kalor untuk MahasiswaTeknik. Salemba Teknika, Jakarta.
Lakitan, Benyamin. 2002. Dasar-dasar Klimatologi, RajaGrafindo Persada,Null.
Leonheart, 2010. http://taufikanugrah.blogspot.com/2010/04/unsur-unsur-cuaca-dan-iklim.html Diakses pada Hari Minggu, 8 November 2014.
LIPI. 2008. Agroklimatologi – Alat dan Prinsip Kerja. http://www.lipi.go.id Diakses pada hari Minggu,15 Mei 2011.
Lizenhs. 2010. http://lizenhs.wordpress.com. Diakses padatanggal 8 November 2014.
Pitts, D. R., and L. E. Sissom, 2001. Theory and Problemsof Heat Transfer. Second Edition
Purwoko. Dkk. 2009. Physic For Senior High School Year X.Semarang: Yudhistira
Runtunuwu 2008. Validasi Model PendugaanEvapotranspirasi : Upaya Melengkapi Sistem DatabaseIklim Nasional. JurnalTanah dan Iklim No. 3 Vol. 27: 8 – 9.
Samadi. 2010. Geography For Senior High School Year X.Semarang: Yudhistira.
Soekardi.2008. Penuntun Praktikum Agroklimatologi. ProgramStudi Agronomi, Fakultas Pertanian, UniversitasSumatera Utara, Medan.
Soemarto, S. D. 2008. Hidrolisa Teknik. Usaha Nasional.SurabayaSoemarto, S. D. 2008. Hidrolisa Teknik. Usaha Nasional.Surabaya.Sudarsono. 2007. Landasan Pemahaman Fisika Atmosfer dan
Unsur-unsur Iklim. Jurnal Klimatologi Dasar, V (2) : 83-96.
Sugiman dan Masri.JURNAL TEKNIK MESIN . Vol. 8, No. 2,Oktober 2006: 49-56
TT. Glen & HH. Lyle. 2008. Pengantar Iklim. Yogyakarta:Gajah Mada University Press
60
Vink, G.J. 2007. Dasar-Dasar Usaha Tani di Indonesia. PT.Midas Surya Grafindo. Jakarta.
Willson, E. M. 2006. Hidrologi Teknik. ITB Bandung.Bandung.
Wisnubroto, Soekardi, dkk. 2007. Asas-Asas MeteorologiPertanian. Ghalia Indonesia. Jakarta.
Wuryanto dkk 2000. Agroklimatologi. USU Press. MedanWuryatno. 2009. Klimatologi Dasar. PT Dunia Pustaka Jaya.
Jakarta.
II. PENGAMATAN UNSUR-UNSUR CUACA SECARA OTOMATIS
A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Iklim adalah rata - rata dari pergantian
atau keadaan cuaca dalam wilayah yang luas dan
jangka waktu yang lama (perhitungan jangka waktu
± 30 tahun). Terjadinya iklim yang bermacam-macam
di muka bumi, disebabkan oleh rotasi dan revolusi
bumi berdasar letak lintang dan ketinggian suatu
tempat (keadaan ini menyebabkan suhu udara di
wilayah lintang rendah atau wilayah khatulistiwa
lebih panas dibanding wilayah lintang tinggi atau
wilayah kutub). Sedangkan cuaca adalah keadaan
udara pada tempat yang sempit dan dalam jangka
waktu yang pendek dan merupakan hasil dari proses
kimia yang dapat berubah. Unsur-unsur cuaca dan
iklim yang diamati pada praktikum di antaranya
adalah radiasi surya, tekanan udara, suhu tanah
dan udara, kelembaban tanah dan udara, curah
hujan, angin, evaporasi, dan awan.
Unsur-unsur dari cuaca dan iklim tersebut
memiliki pengaruh terhadap dunia pertanian, salah
satunya dalam hal penurunan dan peningkatan hasil
produksi. Walaupun kondisi suatu lahan pertanian
subur dan dirawat dengan perawatan maksimal,
namun jika iklim dan cuacanya buruk maka hasil
produksi juga tidak akan normal bahkan cenderung
38
39
gagal. Masa bercocok tanam juga dipengaruhi oleh
maju mundurnya musim, baik musim kemarau maupun
musim hujan.
Di Indonesia pengetahuan tentang cuaca dan
iklim sangatlah penting karena sering kali
terjadi penyimpangan permulaan musim penghujan
yang kemudian sangat mempengaruhi kegiatan
pertanian di Indonesia. Oleh sebab itu pengetahuan
tentang iklim dan cuaca sangatlah diperlukan untuk
memungkinkan dilakukannya eksplorasi potensi iklim
untuk perencanaan intensifikasi dan ekstensifikasi
produksi. Selain itu, pengetahuan akan cuaca dan
iklim juga dapat dimanfaatkan sebagai dasar
strategi penyusunan rencana dan kebijakan
pengelolaaan usaha tani (pola tanam, irigasi,
pemupukan, tindakan modifikasi, shelterbelt dan
lainnya).
2. Tujuan Praktikum
Acara pengamatan unsur cuaca ini dilaksanakan
dengan tujuan :
Mengetahui pengamatan unsur cuaca dan iklim
menggunakan alat dan pengamat cuacaotomatis (AWS =
Automatic Weather Station).
3. Waktu dan Tempat Peraktikum
40
Acara pengamatan unsur-unsur cuaca dengan AWS
dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 8 November
2014. Bertempat di Stasiun Klimatalogi, desa
Sukosari, kecamatan Jumantono, Karanganyar (untuk
mengetahui alat sensor unsur-unsur cuaca)
sedangkan server ada di laboratorium Pedologi
fakultas Pertanian UNS.
B. TINJAUAN PUSTAKAStasiun klimatologi pertanian merupakan
stasiun meteorologi pertanian yang mampu
menyelenggarakan pengamatan cuaca dan biologi dalam
jangka waktu yang panjang dan teratur.Penempatan
stasiun klimatologi harus ada pada setiap titik
jaringan pengamatan internasional secara mantap.
Minimal dalam jangka waktu 10 tahun tidak boleh
dipindahkan. Oleh karena itu,dalam penentuan
lokasinya harus tepat, yaitu lokasi yang mewakili
lingkungan alam yang tidak mudah berubah sehingga
data yang diperoleh dapat terjamin (Suprayogi 2003).
Alat pemantau digital khususnya dibidang
cuaca, yang merupakan kunci dari penyampaian
informasi yang cepat dan akurat ke masyarakat yang
sifatnya secara rutin. AWS (Automatic Weather
Station) merupakan alat pemantau cuaca digital. Alat
ini dilengkapi dengan berbagai sensor meteorologi
dan peralatan komunikasi dan diciptakan untuk
bekerja dilokasi naupun pada kondisi dimana tidak
41
membutuhkan tenaga operator dan tidak bergantung
kepada sumber listrik perumahan (Cahaya 2009).
AWS merupakan seperangkat pengukur anasir
iklim yang bekerja secara otomatis dan terpadu. AWS
dipasang dalam sebuah stasiun meteorologi. Stasiun
meteorologi pertanian adalah suatu tempat yang
mengadakan pengamatan secara terus menerus mengenai
keadaan fisik dan lingkungan atmosfer serta
pengamatan tentang keadaan biologi dari tanaman dan
obyek pertanian lainnya. Dalam hubungan yang lebih
luas, keberadaan stasiun ini sangat penting mencakup
hal-hal yang terkait dengan penetuan ketersediaan
air baik jumlah maupun intensitasnya, penentuan
misim tanam,laju pertumbuhan dan hasil panen,
kebutuhan air irigasi, peramalan terhadap
perkembangan populasi hama dan penyakit, prasyarat
kondisi iklim bagi pertumbuhan dan produksi optimum
suatu tanaman (Chow 2000).
Pengamatan data melalui AWS (Automatic Weather
Station) dapat dilakukan dengan menggunakan PC
(Program Cumulus) serta media pengiriman data
seperti modem dan pesawat telepon atau media
internet. Melalui sistem yang demikian pengkajian
klimatologi dapat dengan lebih mudah dan cepat
dilakukan. Secara terpadu, AWS (Automatic Weather
Station) mengamati unsur-unsur cuaca seperti
42
kecepatan angin, radiasi matahari, suhu dan
kelembaban angin, serta curah hujan (Neufert 2000)
AWS (Automatic Weather Stations) merupakan suatu
peralatan atau sistem terpadu yang di disain untuk
pengumpulan data cuaca secara otomatis serta di
proses agar pengamatan menjadi lebih mudah. AWS ini
umumnya dilengkapi dengan sensor, RTU (Remote
Terminal Unit), Komputer, unitLED Display dan bagian-
bagian lainnya. Sensor-sensor yang digunakan
meliputi sensor temperatur, arah dan kecepatan
angin, kelembaban, presipitasi, tekanan udara,
pyranometer, net radiometer. RTU (Remote Terminal Unit)
terdiri atas data logger dan backup power, yang
berfungsi sebagai terminal pengumpulan data cuaca
dari sensor tersebut dan di transmisikan ke unit
pengumpulan data pada computer (Farensa 2012).
Adapun beberapa sensor yang terdapat pada AWS,
diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Wind Speed ( Kecepatan Angin)
Sensor ini berfungsi untuk mengukur kecepatan
angin yang bergerak secara horisontal. Di dalam
tubuh sensor, sebuah magnet berotasi memproduksi
satu medan magnet penggerak yang membuka dan
menutup sebuah reed switch dua kali setiap
putaran. Data logger menghitung perputaran buka
tutup ini dan mengukur kecepatan angin melalui
jumlah putaran buka tutup perdetiknya. Sensor
43
kecepatan angin terbuat dari stainless steel yaitu
campuran logam aluminium yang dianodakan.
2. Wind Direction (Arah Angin)
Alat ini berfungsi sebagai sensor arah angin
yang seraah horisontal. Arah angin diukur dari
arah utara kompas dengan gerak searah jarum jam.
Rakitan baling-balingnya terdiri dari dua baling-
baling diimbangi oleh penunjuk tahan kerat. Saat
rakitan baling-baling bergerak sesuai arah angin,
presisi potensiometer di dalam sensor mengubah
muatan listriknya. Pemasok data mengukur hambatan
listrik ini dan menentukan posisi baling-baling
berdasarkan pembacaan tersebut.
3. Solar Radiation (Radiasi Matahari)
Alat ini berperan sebagai sensor pengukur
radiasi sinar matahari dengan satuan pengukuran
watt per meter persegi. Radiasi sinar matahari
menyebabkan silikon fotosel menggerakkan tegangan
yang berbanding lurus dengan radiasi matahari.
Pemasok data mengukur tegangan dan mencatat
pembacaan dalam W/m2. Sensor radiasi cahaya
matahari terbuat dari baja anti karat yaitu logam
campuran aluminium yang diberi muatan anoda.
4. Relative Humidity (Kelembaban Nisbi)
Merupakan sensor kelembaban nisbi ini
mengukur muatan lembab pada udara. Kelembaban
nisbi adalah kelembaban sebenarnya sebagai
44
prosentase dari kelembaban maksimum (udara yang
terlembabkan dengan air) saat suhu kamar atau
sekitarnya. Kelembaban diukur dengan menggunakan
sensor film dari polimer yang tipis.
5. Air Temperature (Suhu Udara)
Berfungsi sebagai pengukur suhu udara dengan
menggunakan Platinum Resistance Termometer (PRT).
Sensor ini dipasang di dalam sebuah layar radiasi
yang terlindungi untuk meminimalisir efek-efek
hujan dan radiasi matahari. Hambatan listrik PRT
berubah seiring berubahnya suhu dan pemasok data
dalam mengukur hambatan ini untuk menghitung suhu.
6. Soil Temperature (Suhu Tanah)
Berfungsi sebagai sensor yang mengukur
temperatur suhu tanah pada posisi dalam profil
tanah dimana satelit ditanam. Sensor ini bertipe
termistor yang dibungkus dalam sebuah satelit
stainless stell. Resistensi elektris termistor
berubah seiring berubahnya temperatur dan pemasok
data mengukur resistensi ini untuk menghitung
temperaturnya. Sensor temperatur tanah ini terbuat
dari stainless stell.
7. Raingauge (Curah Hujan)
Merupakan sensor ini mengukur hujan
menggunakan metode ember terbalik. Hujan
dikumpulkan melalui sebuah celah atau lubang
45
berukuran tertentu dan disalurkan ke ember
terbalik yang dibagi saat jumlah curah hujan
sebesar 0,2 mm terkumpul. Ember akan terbalik atau
tumpah sampai kosong. Gerakan ini menutup sebuah
reed switch yang mengirimkan sinyal listrik ke
pemasok data. Belahan ember yang lain kemudian
terisi dan proses ini akan terulang kembali.
Pemasok data mengjitung sinyal listrik untuk
mencatat jumlah curah hujan. Sensor curah hujan
terbuat dari fiberglass dan cetakan plastik yang
terinjeksi.
8. Barometric Pressure (Tekanan Barometer)
Berfungsi sebagai sensor tekanan barometer
mengukur tekanan atmosfer. Sensor ini dipasang
pada papan sirkuit pemasok data di dalam wadah
pelindung (Titus 2011).
46
C. HASIL PENGAMATAN
Gambar 2.1 AWS di Stasiun Klimatalogi
1.Bagian-bagian Utama AWS
a.Panel surya
b.Sensor intensitas radiasi matahari
c.Kotak Baterai
d.Komponen sensor-sensor pengamat unsur-unsur
cuaca meliputi sensor temperatur, arah dan
kecepatan angin, kelembaban, presipitasi,
tekanan udara, pyranometer, net radiometer
e.Key logger
f.Penangkal petir
2.Prinsip Kerja
Komponen sensor seperti sensor temperatur,
arah dan kecepatan angin, kelembapan, presipitasi,
tekanan udara, pyranometer dan radiometer
merupakan komponen utama yang menjalankan fungsi
kerja AWS. Masing-masing sensor tersebut nantinya
secara otomatis menangkap dan mencatat berbagai
unsur iklim sesuai dengan bagiannya masing-masing.
Selanjutnya data-data dari sensor-sensor tersebut
47
nantinya akan dimasukkan ke dalam RTU (Remote
Terminal Unit). Bagian utama RTU adalah data logger
dan backup power, yang berfungsi sebagai terminal
pengumpulan data cuaca dari sensor tersebut dan di
transmisikan ke unit pengumpulan data pada
komputer lewat satelit. Kemudian masing- parameter
cuaca dapat dilihat melalui LED (Light Emittig Diode)
Display, sehingga cuaca dapat diamati secara
otomatis dan mudah.
D. PEMBAHASANAWS (Automatic Weather Stations) merupakan suatu
peralatan atau sistem terpadu yang di disain untuk
pengumpulan data cuaca secara otomatis serta di
proses agar pengamatan menjadi lebih mudah. AWS ini
umumnya dilengkapi dengan sensor, RTU (Remote Terminal
Unit), Komputer, unit LED Display dan bagian-bagian
lainnya. Sensor-sensor yang digunakan meliputi
sensor temperatur, arah dan kecepatan angin,
kelembaban, presipitasi, tekanan udara, pyranometer,
net radiometer.
Peranan AWS di bidang pertanian dapat
mengurangi penggunaan lahan untuk penempatan
berbagai macam alat-alat pengukur seperti
evaporimeter, ombrometer, sunshine recorder, dll.
Selain itu dengan adanya AWS tingkat keakuratan
pengukuran unsur-unsur cuaca lebih besar dibanding
48
alat manual. Hal ini dikarenakan AWS telah
menggunakan sistem komputer, data logger, maupun
jaringan internet. Adanya AWS dapat ditentukan pola
tanam apa yang cocok pada waktu tersebut dan
pastinya tanaman dapat diprediksi masa panennya.
Pelatihan tenaga penyuluh pertanian diperlukan untuk
membantu menganalisis data cuaca serta
interpretasinya guna penyuluhan pertanian sebagai
bagian program pembangunan pertanian di Indonesia
AWS memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan
pencatatan manual konvensional antara lain AWS lebih
konsisten dalam pengukuran, AWS menyediakan data
pada frekuensi secara signifikan lebih besar
(beberapa menyediakan data setiap menit), AWS
menyediakan data dalam segala cuaca, siang dan
malam, 365 hari per tahun, dan AWS dapat dipasang di
daerah yang jarang penduduknya. Namun, AWS memiliki
kelemahan, antara lain beberapa elemen yang sulit
untuk mengotomatisasi contohnya awan, AWS
membutuhkan investasi modal besar, dan AWS kurang
fleksibel daripada pengamat manusia. Kelebihan
maupun kekurangan yang akan diuraikan di bawah ini.
1. Kelebihan AWS
a. Praktis dan mudah dalam pengambilan data
49
b. Standarisasi pengamatan (time and quality)
c. Pengamatan real time secara kontinyu tanpa
putus baik siang ataupun malam hari.
d. Data lebih akurat.
e. Data lebih reliable(dapat dipercaya).
f. Penyimpanan data secara otomatis.
g. Resolusi lebih tinggih.
h. Kemampuan penyimpanan data lebih besar.
i. Tidak subjektif.
j. Penyimpanan data dapat dilakukan sampai
kondisi cuaca yang ekstrem
k. Tidak ada kesalahan pembacaan
2. Kekurangan AWS
a. Harus dilakukan pemeliharan rutin.
b. Harus dikalibrasi periodik.
c. Dibutuhkan tenaga teknisi yang handal dan
ahli untuk mengoperasikan.
d. Dibutuhkan software agar data cuaca tersebut
dapat dibaca.
e. Harga peralatan dan operasional yang cukup
tinggi.
f. Luas daerah yang dipresentasikan terbatas,
sekitar 3-5 km dari lokasi.
50
E. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
a. Mengetahui unsur cuaca dan iklim menggunakan
alat pengamat cuaca otomatis yaitu AWS
b. AWS (Automatic Weather Station) merupakan
suatu peralatan atau sistem terpadu yang di
desain untuk pengumpulan data cuaca secara
otomatis serta di proses agar pengamatan
menjadi lebih mudah
c. AWS dapat mengukur sekaligus beberapa unsur-
unsur cuaca tanpa perlu diawasi secara langsung
(24 jam), melainkan dapat diawasi melalui
jaringan internet
d. Tingkat keakuratan AWS lebih tinggi
dibandingkan alat-alat pengukur manual lainnya.
e. Adanya AWS dapat mengukur unsur-unsur cuaca
seperti kadar curah hujan secara detail namun
pada kenyataanya semakin umur AWS yang semakin
tua, menyebabkan keakuratan data yang diperoleh
menjadi berkurang.
2. Saran
Perbaikan peralatan pengukur cuaca otomatis
yang ada di Stasiun Klimatologi Desa Sukosari,
Kecamatan Jumantono, Karanganyar untuk segera
dilakukan untuk menunjang pengembangan sistem
informasi meteorologi pertanian agar dapat
52
DAFTAR PUSTAKA
Chow VT. 2000. A Method for The Practical Application of The PenmanFormula for The Estimation of ET from Free Water Surface. FAOof UNO. Hlm 20.
Edi S, Cahaya. 2009. Rancang Bangun Sensor Suhu Tanah dan Kelembaban Udara. Jurnal Sains Dirgantara Vol. 7 No. 1 Desember 2009 : 201-212.
Farensa. 2012. Diakses dari http://farensapetanisukses1.blogspot.com pada tanggal 8 November 2013.
Neufert E. 2000. Architects Data. New York:Halsted Press.Prawirowardoyo, S. 2000. Meteorologi. Institut Teknologi Bandung: Bandung
Rendy B, Titus dkk. 2011. Pengenalan Stasiun Meteorologi Pertanian Khusus dan Peralatan Pengamatan Cuaca. Diakses dari http://dmiraclesofmylive.blogspot.com/2011_01_01_archive.html.pada tanggal 8 November 2013.
Suprayogi S, Setiawan BI, Prasetyo LB. 2003. PenerapanBeberapa Model Evapotranspirasi di DaerahTropika. Jurnal Keteknikan Pertanian 17(2):7-13.
III. PENGUKURAN SUHU TANAH
A. PENDAHULUAN
1. Latar BelakangSuhu adalah tingkat kemampuan benda dalam
memberi atau menerima panas. Suhu seringkali juga
dinyatakan sebagai energi kinetis rata-rata suatu
benda yang dinyatakan dalam derajat. Suhu juga
dinyatakan sebagai ukuran energi kinetik rata-
rata dari pergerakkan molekul suatu benda. Suhu
menunjukkan sangkar cuaca yang dipergunakan untuk
pengamatan suhu.
Suhu tanah adalah salah satu faktor
terpenting yang dapat mendukung aktivitas
mikrobiologi dan proses penyerapan unsur hara
oleh tanaman. Suhu tanah sangat bergantung pada
besarnya radiasi surya yang di berikan oleh
matahari. Dalam biosfer, suhu benda alami,
beragam menurut tempat dan waktu yang disebabkan
oleh perbedaan benda dalam menerima energi
radiasi surya dan hasil pengaruh energi ini
terhadap sekelilingnya. Menurut tempat ia
ditentukan oleh letak menurut ketinggian dan
menurut lintang di bumi. Menurut waktu ia
ditentukan oleh sudut inklinasi surya.
Suhu tanah adalah jumlah keseluruhan
intensitas yang notabene adalah kombinasi emisi
panjang gelombang dan aliran panas dalam tanah.
47
48
Suhu tanah sering juga disebut intensitas panas
dalam tanah dengan satuan derajat Celcius,
derajat Fahrenheit, derajat Kelvin dan lain-lain.
Pengukuran dilakukan dengan menggunakan
thermometer air raksa dan alkohol. Dengan
thermometer air raksa pengukuran dapat dilakukan
dari suhu 35°C – 350°C, hasilnya adalah cukup
bagus karena mengingat angka pengembangan air
raksa pada tiap suhu lebih merata dari alkohol,
sehingga untuk pengukuran suhu udara biasanya
digunakan termometer air raksa.
2. Tujuan PraktikumTujuan praktikum pengukuran suhu tanah yaitu
untuk mengetahui suhu tanah pada pertanaman
dengan perlakuan pemberian mulsa organik (jerami
padi).
3. Waktu dan Tempat Praktikum
Acara pengukuran suhu tanah dilaksanakan pada
hari Sabtu, tanggal 8 November 2014. Bertempat di
kebun percobaan Fakultas Pertanian UNS, desa
Sukosari, kecamatan Jumantono, kabupaten
Karanganyar.
B. Tinjauan Pustaka
Temperatur (suhu) adalah salah satu sifat tanah
yang sangat penting secara langsung mempengaruhi
pertumbuhan tanaman dan juga terhadap kelembapan,
aerasi, stuktur, aktifitas mikroba, dan enzimetik,
49
dekomposisi serasah atau sisa tanaman dan
ketersidian hara-hara tanaman. Tenperatur tanah
merupakan salah satu faktor tumbuh tanaman yang
penting sebagaimana halnya air, udara dan unsur
hara. Proses kehidupan bebijian, akar tanaman dan
mikroba tanah dipengaruhi oleh temperatur tanah
(Hanafiah 2005). Tentang suhu tanah pengaruhnya
penting sekali pada kondisi tanah itu sendiri dan
pertumbuhan tanaman. Pengukuran dari suhu tanah
biasanya dilakukan pada kedalaman 5 cm, 10 cm, 20
cm, 50 cm, dan 100 cm. Faktor pengaruh suhu tanah
yaitu faktor luar dan faktor dalam. Yang dimaksud
dengan faktor luar yaitu radiasi matahari, awan,
curah hujan, angin, kelembapan udara. Faktor
dalamnya yaitu faktor tanah, struktur tanda, kadar
iar tanah, kandungan bahan organik, dan warna tanah.
Makin tinggi suhu maka semakin cepat pematangan pada
tanaman (Kartasapoetra 2005).
Suhu tanah beraneka ragam dengan cara khas pada
perhitungan harian dan musiman. Fluktasi terbesar
dipermukaan tanah dan akan berkurang dengan
bertambahnya kedalaman tanah. Kelembapan waktu
musiman yang jelas terjadi, karena suhu tanah
musiman lambat bantuk fluktasi suhu pada peralihan
suhu diudara atau dibawah tanah yang lebih besar.
Suhu total untuk semalam tanaman mungkin terjadi
pada tengah hari. Dibawah 6 inch atau 15 inch
50
terdapat variasi harian pada suhu tanah
(Sostrodarsono 2006).
Mulsa jerami atau mulsa yang berasal dari sisa
tanaman lainnya mempunyai konduktivitas panas rendah
sehingga panas yang sampai ke permukaan tanah akan
lebih sedikit dibandingkan dengan tanpa mulsa atau
mulsa dengan konduktivitas panas yang tinggi seperti
plastik. Jadi jenis mulsa yang berbeda memberikan
pengaruh berbeda pula pada pengaturan suhu,
kelembaban, kandungan air tanah, penekanan gulma dan
organisme pengganggu. Namun manipulasi lingkungan
tumbuh dengan cara teknik budidaya tersebut akan
berbeda pengaruhnya jika dilakukan pada tanaman
kentang dengan kultivar yang berbeda, begitu juga
perbedaan jenis mulsa akan berbeda pengaruhnya
terhadap perbedaan lingkungan terutama suhu tanah
sehingga pertumbuhan dan hasil tanaman kentang untuk
tiap kultivar akan berbeda pula (Hamdani 2009).
Penanaman tanaman penutup tanah dan penutupan
permukaan tanah dengan sisa-sisa tanaman merupakan
teknik konservasi secara vegetatif/kultur teknis
yang mudah dilaksanakan. Adanya tanaman penutup
tanah dan mulsa organik dapat menahan percikan air
hujan dan aliran air di permukaan tanah sehingga
pengikisan lapisan atas tanah dapat ditekan. Adanya
mulsa akan dapat mampu memelihara struktur tanah,
meningkatkan infiltrasi tanah, mengurangi pencucian
51
hara dan menekan pertumbuhan gulma sehingga akan
menambah kemampuan tanah dalam mendukung tanaman
yang ada di atasnya sehingga hasil usaha taninya
baik dan dengan adanya mulsa dapat memantulkan
cahaya matahari ke tanaman sehingga tanaman yang ada
secara keseluruhan akan terkena sinar matahari
(Sumarni, dkk 2005).
C. ALAT, BAHAN DAN CARA KERJA
1. Alat
a. Termometer tanah
2. Bahan
a. Petak pertanaman jagung
b. Mulsa jerami
c. Mulsa plastik bening
d. Mulsa plastik perak biasa
3. Cara Kerja
Mengukur suhu tanah (menggunakan termometer
tanah) pada petak pertanaman jagung degan
beberapa perlakuan :
a. Kontrol (lahan terbuka)
b. Petak pertanaman jagung tanpa mulsa
c. Petak pertanaman jagung yang diberi mulsa
jerami
d. Petak pertanaman jagung yang diberi mulsa
plastik bening
e. Petak pertanaman jagung yang diberi mulsa
plastik perak biasa
52
D. HASIL PENGAMATAN
Tabel 3.1 Hasil Pengamatan Suhu di Jumantono
NO JAMSUHU TANAH (°C)
ORGANIK PLASTIK
HITAMPERAK
COVERCROP KONTROL
1 7.30 31 33 32 32 30
2 8.30 31,9 35 32,7 32 37
3 9.30 32 38 35 33,5 38
410.30 33 40 36 34 39
511.30 33 41 38 35 40
612.30 34 45 38 37 42
713.30 35 49 47 40 46
Sumber: Rekapan Data
E. PEMBAHASAN
Tanah terdiri atas hancuran batu-batuan. Sifat-
sifat tanah bergantung pada besar kecilnya partikel-
partikel yang merupakan komponen-komponen tanah
tersebut. Tanah mengandung partikel-partikel
mineral, sisa-sisa tanaman dan binatang, air,
berbagai gas dan komposisi lainnya yang menjadikan
tanah tersebut menjadi subur, yang menjamin
berlangsungnya kehidupan berbagai makhluk di bumi.
Suhu tanah merupakan hasil dari keseluruhan
radiasi yang merupakan kombinasi emisi panjang
53
gelombang dan aliran panas dalam tanah. Suhu tanah
juga disebut intensitas panas dalam tanah dengan
satuan derajat Celcius, derajat Fahrenheit, derajat
Kelvin dan lain-lain. Suhu tanah ditentukan oleh
interaksi sejumlah faktor. Faktor eksternal
(lingkungan) dan internal (tanah) menyumbang
perubahan-perubahan suhu tanah. Semua panas tanah
berasal dari dua sumber yaitu radiasi matahari dan
awan dan konduksi dari dalam bumi.
Suhu biasanya diamati pada kedalaman 5, 10, 20,
50, dan 100 cm. Untuk keperluan ini telah dibuat
termometer sesuai dengan kedalamannya. Pengukuran
suhu tanah dilakukan pada tanah yang tertutup oleh
rumput maupun tanah yang terbuka. Pengukuran
biasanya dilakukan dalam areal stasiun pengamatan.
Areal tidak boleh ternaungi dan tergenang air, hal
ini harus dihindari. Termometer dilindungi dengan
pagar kawat dan dijaga agar tanah disekitarnya tidak
terganggu.
Prinsip kerja termometer tanah hampir sama
dengan termometer biasa, hanya bentuk dan panjangnya
berbeda. Pengukuran suhu tanah lebih teliti daripada
suhu udara. Perubahannya lambat sesuai dengan sifat
kerapatan tanah yang lebih besar daripada udara.
Sampai kedalaman 20 cm digunakan termometer air
raksa dalam tabung gelas dengan bola ditempatkan
pada kedalaman yang diinginkan. Ciri-ciri dari
54
termometer tanah adalah pada bagian skala
dilengkungkan.halini dibuat adalah untuk memudahkan
dalam pembacaan termometer dan menghindari
kesalahan paralaks. Termometer tanah untuk kedalaman
50 cm dan 100 cm bentuknya berbeda dengan kedalaman
lain. Termometer berada dalam tabung gelas yang
berisi parafin, kemudian tabung diikat dengan rantai
lalu diturunkan dalam selongsong tabung logam ke
dalam tanah sampai kedalaman 50 cm atau 100 cm.
Pembacaan dilakukan dengan mengangkat
termometer dari dalam tabung logam, kemudian dibaca.
Adanya parafin memperlambat perubahan suhu ketika
termometer terbaca di udara. Termometer tanah pada
kedua kedalaman ini bila merupakan suatu kapiler
yang panjang dari mulai permukaan tanah, mudah
sekali patah apabila tanah bergerak turun atau pecah
karena kekeringan.
Pada praktikum kali ini dilakukan lima
perlakuan dalam mengukur suhu tanah, yaitu pada
tanah (sebagai kontrol), mulsa plastic hitam, mulsa
plastic bening, mulsa organic, dan Cover croop
(rumput). Berdasarkan data yang telah diperoleh,
dapat dilihat bahwa semakin siang suhu tanah semakin
tinggi. Pada tanah (control) terjadi fluktuasi suhu
yang cukup tinggi, sedangkan pada perlakuan lainnya
juga terjadi fluktuasi suhu tetapi hanya sedikit,
hal ini disebabkan karena mulsa plastic hitam, mulsa
55
plastic bening, mulsa organic dan rumput berfungsi
untuk menjaga kestabilan suhu dalam tanah baik pada
siang hari maupun malam hari sehingga tanaman dapat
tumbuh dengan baik.
F. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
a. Suhu tanah merupakan hasil dari keseluruhan
radiasi yang merupakan kombinasi emisi panjang
gelombang dan aliran panas dalam tanah.
b. Suhu tanah juga disebut intensitas panas
dalam tanah dengan satuan derajat Celcius,
derajat Fahrenheit, derajat Kelvin dan lain-
lain.
c. Semua panas tanah berasal dari dua sumber
yaitu : Radiasi matahari dan awan serta Konduksi
dari dalam bumi.
d. Alat untuk mengukur suhu tanah adalah
thermometer tanah. Prinsip kerja termometer
tanah hampir sama dengan termometer biasa, hanya
bentuk dan panjangnya berbeda.
e. Pemberian mulsa pada tanah bertujuan untuk
menjaga kestabilan suhu dalam tanah.
2. Saran
Tanah merupakan tempat bertumbuhnya tanaman.
Untuk itu diperlukan pembelajaran tentang tanah
khususnya suhu tanah. Tanaman untuk tumbuh dengan
baik ditanam pada tanah yang fluktuasi suhu antara
56
siang dan malam yang kecil, dan untuk itu
diperlukan cara untuk mencegah fluktuasi yang
besar pada tanah salah satunya dengan menggunakan
mulsa. Penggunaan mulsa pada tanah sangat membantu
petani dalam usaha taninya sehingga hal ini juga
akan mempengaruhi perbaikan ekonomi petani.
57
DAFTAR PUSTAKA
Hanafiah K 2005. Dasar-Dasar Ilmu Tanah. Jakarta : PT. RajaGrafindo
PersadaHamdani, Jajang Sauman. 2009. Pengaruh Jenis Mulsa
terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tiga KultivarKentang. J. Agron. Indonesia 37 (1) : 14 – 20 (2009)
Kartasapoetra, AG. 2004. Klimatologi : Pengaruh Iklim terhadapTanah dan Tanaman Edisi Revisi. Bumi Aksara. Jakarta.
Sostrodarsono. 2006. Tahapan Tahapan Menuju Pertanian Terpadudan Berkelanjutan. Edu Media. Purworejo
Sumarni,N., A. Hidayat, danE. Sumiati. 2005. PengaruhTanaman Penutup Tanah dan Mulsa Organik terhadapProduksi Cabai dan Erosi Tanah. J.Hort. 16(3):197-201,2006.
IV. PENGARUH ANGIN TERHADAP EVAPOTRANSPIRASI
A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Kecepatan angin (v) Angin merupakan faktor
yang menyebabkan terdistribusinya air yang telah
diuapkan ke atmosfir, sehingga proses penguapan
dapat berlangsung terus sebelum terjadinya
keejenuhan kandungan uap di udara,
Evaporasi adalah proses pertukaran molekul
air dipermukaan menjadi molekul uap air
diatmosfir melalui kekuatan panas. Evaporasi
dapat terjadi pada sungai, danau, laut,reservoir
atau permukaan air bebas, serta permukaan tanah.
Penguapan merupakan proses yang melibatkan
pindahpanas dan pindah massa secara simultan.
Faktor terebut memberikan pengaruh terhadap
laju transpirasi tanaman. Dapat dikatakan bahwa
ketiga prosesdi atas merupakan hal yang sangat
penting yang menentukan kualitas tanaman. Maka
dari itu ketiga proses di atas perlu diprlajari
untuk kemajuan pertanian.
Oleh sebab itu, pengetahuan tentang pengaruh
angin terhadap evapotranspirasi yang terjadi pada
tumbuhan penting dalam mempelajari keseimbangan
hidrologi
2. Tujuan Praktikum
53
54
Acara praktikum pengaruh angin terhadap
evapotranspirasi adalah untuk mengetahui pengaruh
kecepatan angin terhadap besarnya
evapotransipirasi.
3. Waktu dan Tempat Praktikum
Acara pengamatan pengaruh angin terhadap
evapotranspirasi dilaksanakan pada hari Minggu,
tanggal 9 November 2014. Bertempat di kebun
Fakultas Pertanian UNS, desa Sukosari, kecamatan
Jumantono, kabupaten Karanganyar.
55
B. Tinjauan Pustaka
Evaporasi adalah perubahan air menjadi uap,
yang merupakan suatu proses yang berlangsung hampir
tanpa gangguan selama berjam-jam pada siang hari dan
sering juga selama malam hari.Uap ini kemudian
bergerak dari permukaan tanah atau permukaan air ke
udara. Evapotranspirasi merupakan ukuran total
kehilangan air untuk suatu luasan lahan melalui
evaporasi dari permukaan tanaman. Secara potensial
evapotranspirasi ditentukan hanya oleh unsur – unsur
iklim, sedangkan secara aktual evapotranspirasi juga
ditentukan oleh kondisi tanah dan sifat tanaman
(Karmini 2008).
Evaporasi adalah komponen utama penggerak
siklus hidrologi, karena itu menduga laju evaporasi
dengan akurat sangat penting untuk pengelolaan
sumber daya air dan peningkatan produksi pertanian.
Tetapi, laju evaporasi adalah unsure iklim yang
sulit diukur secara langsung karena beragamnya
faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang
mempengaruhi ET adalah faktor cuaca seperti radiasi
matahari, suhu udara, kelembaban udara dan kecepatan
angin; faktor tanaman seperti jenis tanaman, fase
tumbuh, keragaman dan kerapatan tanaman dan faktor
pengelolaan dan kondisi lingkungan tanaman seperti
kondisi tanah, salinitas, kesuburan tanah, tingkat
56
serangan hama dan penyakit pada tanaman
(Temesken, Davidovv dan Frame 2005).
Evaporasi merupakan proses fisis perubahan
cairan menjadi uap, hal ini terjadi apabila air cair
berhubungan dengan atmosfer yang tidak jenuh, baik
secara internal pada daun (transpirasi) maupun
secara eksternal pada permukaan-permukaan yang
basah. Suatu tajuk hutan yang lebat menaungi
permukaan di bawahnya dari pengaruh radiasi matahari
dan angin yang secara drastis akan mengurangi
evaporasi pada tingkat yang lebih rendah.
Transpirasi pada dasarnya merupakan salah satu
proses evaporasi yang dikendalikan oleh proses
fotosintesis pada permukaan daun (tajuk). Perkiraan
evapotranspirasi adalah sangat penting dalam kajian-
kajian hidrometeorologi (Juwita 2010).
Istilah evaporasi yang sering digunakan di
dalam studi agroklimatologi adalah evaporasi (Epan),
yang menggambarkan jumlah air menguap dari permukaan
air langsung ke atmosfir, evapotranspirasi aktual
(ETa), yang menggambarkan jumlah air pada permukaan
tanah yang berubah menjadi uap air pada kondisi
normal, dan evapotranspirasi potensial (ETp) adalah
kehilangan air yang terjadi untuk memenuhi kebutuhan
vegetasi yang terjadi pada saat kondisi air tanah
jenuh (Runtunuwu et al., 2008).
57
Evapotranspirasi merupakan salah satu mata
rantai dalam siklus hidrologi dan komponen penting
dalam perhitungan kebutuhan dan ketersediaan air.
Metode untuk mengestimasi evapotranspirasi biasanya
dilakukan pertitik dengan tutupan lahan dianggap
homogen sehingga estimasi evapotranspirasi untuk
wilayah yang luas bisa menyebabkan ketidakakuratan,
untuk mengatasi masalah ini diaplikasikan
penginderaan jauh dengan estimasi evapotranspirasi
per piksel. Pada penelitian ini diaplikasikan
pengolahan citra satelit kedalam perhitungan
evapotranspirasi untuk memperoleh hasil estimasi
evapotranspirasi spasial (Bituk 2009).
C. ALAT, BAHAN DAN CARA KERJA
1. Alat
a. Anemometer
b. Pematah angin
c. Alat tulis
2. Bahan
a. Tanaman jagung
3. Cara Kerja
a. Melakukan pengamatan kecepatan angin pada petak
pertanaman jagung tanpa pematah angin.
b. Melakukan pengamatan kecepatan angin pada petak
pertanaman jagung yang pada bagian tepi luarnya
dipasang pematah angin.
58
c. Menghitung besarnya evapotranspirasi pada kedua
petak dengan rumus Blaney-Cridle
d. Membandingkan besarnya evapotranspirasi pada
kedua petak pertanaman jagung.
D. HASIL PENGAMATAN
Tabel 4.1 Hasil Pengamatan Kecepatan Angin di
Jumantono
Mingg
u Kecepatan Angin (m/s)
Suhu Rata-rata
Harian (°C)
ke-
Tanpa
Pematah
Pematah
Angin
Pematah
Angin
Tanpa
Pematah
1 0,6 0,55 36 35
2 1,48 1,38 40 38
3 0,92 0,63 40 39
4 1,08 0,18 41 39
Rerat
a 1,02 0,69
39,3 37,8
Sumber Data Rekapan
Perhitungan evapotranspirasi dengan Rumus Blaney-
Criddle:
Etc pematah angin = c [ p (0,46T + 8) ] mm
= 0,6 [(0,28(0,46 x 39,3 + 8)]
59
= 0,6 ( 0,28( 26,078))
= 4,38 mm/hari
Etc tanpa pematah angin = c [ p (0,46T + 8) ]
mm
= 0,6 [ 0,28(0,46 x 37,8 +
8) ]
= 0,6 (0,28 (25, 388))
= 4,26 mm/hari
Jadi dapat disimpulkan bahwa pada perlakuan
lahan pematah angin laju evapotranspirasi lebih
tinggi.
E. PEMBAHASAN
Evaporasi adalah proses perubahan molekul di
dalam keadaan cair (contohnya air) dengan spontan
menjadi gas (contohnya uap air). Proses transpirasi
adalah hilangnya uap air dari permukaan tumbuhan..
Evapotranspirasi adalah perpaduan antara evaporasi
dari permukaan tanah dengan transpirasi dari tumbuh-
tumbuhan. Besarnya laju evapotranspirasi berbeda-
beda, tergantung dari kadar kelembaban tanah dan
jenis tumbuh-tumbuhan. Transpirasi dan evaporasi
dari permukaan tanah bersama-sama disebut
evapotranspirasi atau kebutuhan air. Jika air yang
tersedia dalam tanah cukup banyak maka
60
evapotranspirasi itu disebut evapotranspirasi
potensial. Mengingat faktor-faktor yang mempengaruhi
evapotranspirasi itu banyak dan lebih sulit daripada
faktor yang mempengaruhi evaporasi maka banyaknya
evapotranspirasi tidak dapat diperkirakan dengan
teliti. Akan tetapi evapotranspirasi adalah faktor
dasar untuk menentukan kebutuhan air dalam rencana
irigasi dan merupakan proses yang penting dalam
siklus hidrologi. Oleh sebab itu maka telah banyak
jenis dan cara penentuannya yang telah diadakan.
Berdasarkan pengamatan pengaruh angin terhadap
evapotranspirasi ini dengan melakukan pengamatan
kecepatan angin pada petak pertanaman jagung tanpa
pematah angin dan pada petak pertanaman jagung yang
pada bagian tepi luarnya dipasang pematah angin.
Pengamatan ini dilakukan selama empat minggu.
Berdasarkan hasil pengamatan tersebut dapat
diketahui kecepatan angin pada petak pertanaman
jagung dengan atau tanpa pematah angin dapat
dihitung besarnya evapotranspirasi pada kedua petak
dengan rumus Blaney-Cridle. Rumusnya yaitu
Etc=c[p(0,46T+8)] dengan satuan mm/hari. Dengan:
Etc = Evapotranspirasi crop
C = Koefisien tanaman bulanan (jagung=0,6)
P = Rata-rata presentase dari jumlah jam
siang tahunan, besarnya didapat dari
tabel, dicari berdasarkan bulan dan letak
61
lintang (misal buan januari, 40°LS maka
P=0,33)
T = Suhu rata-rata harian (°C)
F. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
a. Evapotranspirasi adalah penjumlahan dari
evaporasi (penguapan air secara umum dari suatu
permukaan benda) dan transpirasi (kehilangan
air dalam bentuk uap yang melewati tubuh
tumbuhan).
b. Kecepatan angin mempengaruhi laju
evapotranspirasi. Kecepatan angin yang tinggi
akan menyebabkan laju evapotranspirasi yang
tinggi pula.
c. Jadi suhu, kelembaban relative dan intensitas
cahaya sangat berpengaruh terhadap laju
evaporasi tanah, transpirasi dan
evapotranspirasi tanaman.
d. Intensitas cahaya dan suhu berbanding lurus
dengan laju evapotranspirasi. Semakin rendah
intensitas cahaya, suhu juga semakin rendah
namun kelembaban semakin tinggi dan laju
evapotranspirasi semakin rendah.
2. Saran
Penambahan alat untuk pengukuran, sehingga
dapat dimanfaatkan oleh banyak kegiatan praktikum
dan tidak saling menunggu, karena dapat membuag
63
DAFTAR PUSTAKA
Bituk. 2009. Evapotranspirasi. http://bituk.blogspot.com.Diakses pada tanggal 27 November 2012 padapukul 19.30 WIB.
Juwita. 2010. Evapotranspirasi.http://juwitacantik.wordpress.com. Diakses pada tanggal27 November 2012 pukul 19.30 WIB.
Karmini. 2008. Validasi ModelPendugaanEvapotranspirasi :UpayaMelengkapiSistemDatabase IklimNasional. Jurnal Tanah danIklim.No.27,2008.
Runtunuwu, E., Syahbuddin, H., dan A. Pramudia. 2008.Validasi model pendugaan evapotranspirasi : upayamelengkapi sistem database iklim nasional.JurnalTanah dan Iklim 27: 8 – 9.
V. MODIFIKASI IKLIM MIKRO PERTANAMAN
A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Hampir semua jenis tanaman pertanian ditanam
pada lapangan terbuka, sehingga mereka akan
menerima pengaruh-pengaruh alamiah yang ada di
sekitarnya, baik tanah, iklim, maupun faktor
lainnya. Telah diketahui bersama bahwa tanaman
tidak mungkin pindah dari satu tempat ke tempat
lain yang lebih cocok.
Seseorang akan berusaha untuk menanam suatu
jenis tanaman di tempat-tempat yang iklimnya
dianggap paling cocok (tahap penyesuaian). Namun
karena mengingat makin meningkatnya kebutuhan
orang akan hasil tanaman, tempat-tempat yang
paling cocok untuk suatu jenis tanaman akhirnya
tidak lagi memadai untuk mencakup kebutuhan.
Akibatnya orang akan berusaha untuk menanam
tanaman-tanaman yang dibutuhkan di tempat-tempat
yang iklimnya kurang sesuai. Agar usaha ini dapat
mencapai sasaran, maka diadakan modifikasi iklim
untuk mendekati kebutuhan iklim tanaman yang
optimal. Modifikasi ini ditujukan tehadap iklim
mikro yang merupakan bagian lingkungan yang
59
60
sangat erat hubungannya dengan tempat hidup
tanaman.
Sebagai mahasiswa Fakultas Pertanian,
praktikum agroklimatologi yang di laksanakan
memiliki tujuan bahwa, para mahasiswa di harapkan
memiliki kemampuan dalam mengamati, memahami dan
mengetahui tentang keadaan unsur-unsur cuaca dan
iklim di sekitarnya. Diharapkan para mahasiswa
dapat mengaplikasikan ilmunya untuk peningkatan
usaha pertanian dan di harapkan kedepannya para
mahasiswa dapat melakukan percobaan tentang
memodifikasi cuaca dalam skala mikro untuk
mengembangkan dan meningkatkan kualitas pertanian
di Indonesia.
61
2. Tujuan Praktikum
Acara modififikasi iklim mikro pertanaman ini
bertujuan untuk mengetahui pengaruh jarak tanam
dan nauan terhadap kondisi iklim mikro di dalam
pertanaman.
3. Waktu dan Tempat Praktikum
Acara pengamatan modifikasi iklim mikro
pertanaman dilaksanakan pada hari Minggu,
tanggal 9 November 2014. Bertempat di kebun
Fakultas Pertanian UNS, desa Sukosari, kecamatan
Jumantono, kabupaten Karanganyar.
B. TINJAUAN PUSTAKAIklim mikro merupakan kondisi iklim pada suatu
ruang yang sangat terbatas, tetapi komponen iklim
ini penting artinya bagi kehidupan tumbuhan,
hewan, dan manusia, karena kondisi udara pada
skala mikro ini yang akan berkontak langsung dan
mempengaruhi secara langsung makhluk hidup
tersebut. Keadaan unsur-unsur iklim ini akan
mempengaruhi tingkah laku dan metabolisme yang
berlangsung pada tubuh makhluk hidup, sebaliknya
keberadaan makhluk tersebut (terutama tumbuhan)
akan pula mempengaruhi keadaan iklim mikro di
sekitarnya. Antara makhluk hidup dan udara di
sekitarnya akan terjadi saling mempengaruhi satu
sama lain (Oktavia 2009).
62
Iklim menunjukkan keadaan semula jadi yang
berakitan dengan atmosfer di setiap kawasan yang
berkait rapat dengan cuaca seperti suhu,
kelembaban, taburan hujan, arah dan kelajuan
angin. Iklim mikro pula menunjukkan kepada kedaan
iklim bagi suatu kawasan kecil atau iklim
tempatan, misalnya iklim Malaysia adalah salah
satu dari keadaan iklim mikro yang menjadi
pecahan kepada iklim dunia (Ahmad 2003).
Tanaman atau vegetasi secara langsung
memberikan pengaruh kepada kondisi iklim mikro.
Iklim mikro yang ada melalui modifikasi radiasi
matahari dan suhu tanah. Keberadaan tanaman juga
mempengaruhi tingkat evapotranspirasi (Villegas
et al 2010).
Memodifikasi iklim mikro di sekitar tanaman
terutama tanaman hortikultura merupakan suatu
usaha yang telah banyak dilakukan agar tanaman
yang dibudidayakan dapat tumbuh dan berkembang
dengan baik. Kelembaban udara dan tanah, suhu
udara dan tanah merupakan komponen iklim mikro
yang sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, dan
masing-masing berkaitan mewujudkan keadaan
lingkungan optimal bagi tanaman (Noorhadi, et al
2003).
Radiasi dan lama penyinaran matahari merupakan
anasir yang terpenting dalam kajian iklim mikro.
63
Jumlah radiasi matahari yang sampai ke permukaan
bumi tergantung antara lain kepada konstante
matahari dan keadaan atmosfer, sedangkan lama
penyinaran matahari yang ditentukan oleh keadaan
atmosfer sangat berperan dalam menentukan jumlah
radiasi matahari yang sampai permukaan bumi.
Ditinjau dari kebutuhan terhadap lama penyinaran
matahari, tanaman digolongkan menjadi (Garner dan
Alland, 1920 cit. Wisnubroto, 1981):
1. Tanaman hari panjang yang memerlukan lama
penyinarn lebih dari 14 jam,
2. Tanaman hari pendek, memerlukan lama
penyinaran kurang dari 10 jam,
3. Tanaman hari netral, lama penyinaran antara
10-18 jam, dan
4. Tanaman intermedier memerlukan lama
penynaran selama 12-14 jam.
Anasir iklim yang juga mengendalikan iklim
mikro adalah kelembaban udara. Kelembaban udara
menyatakan banyaknya uap air dalam udara. Uap air
ini merupakan komponen udara yang sangat penting
jika ditinjau dari segi cuaca dan iklim. Sebagian
gas-gas yang menyusun atmosfer yang dekat dengan
permukaan laut relatif konstan dari satu tempat
ke tempat yang lain, sedangkan uap air merupakan
bagian yang tidak konstan, bervariasi antara 0%
sampai 5% . Adanya variabilitas kandungan uap air
64
ini dalam udara baik berdasarkan tempat maupun
waktu penting karena (Wisnubroto et al 1983):
1. Besarnya jumlah uap air dalam udara
merupakan indikator kapasitas potensial
atmosfer tentang terjadinya presipitasi,
2. Uap air mempunyai sifat menyerap radiasi
bumi sehingga ia akan menentukan cepatnya
kehilangan panas dari bumi dan dengan
sendirinya juga akan mengatur temperatur, dan
3. Makin besar jumlah air dalam udara makin
besar jumlah energi potensial yang laten
tersedia dalam atmosfer dan merupakan sumber
terjadinya hujan angin (storm), sehingga dapat
menentukan apakah udara itu kekal atau tidak.
C. ALAT, NAHAN DAN CARA KERJA
1. Alat
a. Lightmeter
b. Anemometer
c. Thermometer
d. Alat tulis
2. Bahan
a. Tanaman jagung
b. Mulsa hitam
c. Paranet
3. Cara Kerja
a. Melakukan penanaman jagung pada petak tanam
dengan jarak 50 cm x 40 cm.
65
b. Melakukan penanaman jagung pada petak yang
lain dengan jarak tanam 25 cm x 40 cm.
c. Melakukan pengamatan Intensitas radiasi, suhu
udara, kecepatan angin dan kelembaban udara
pada ketiga petak pertanaman tersebut.
66
D. HASIL PENGAMATAN
Tabel 5.1 Hasil Pengamatan Iklim Mikro di JumantonoMinggu Suhu (°C)
KelembabanUdara (%)
IntensitasRadiasi
Kec Angin(m/s)
ke-50X40
25X40
Paranet
50X40
25X40
Paranet
50X40
25X40
Paranet
50X40
25X40
Paranet
1 35 34 29 28 28 4082900
81000
63800 1,4
1,39
0,83
2 38 37 34 24 27 29138000
124100
101100
1,51
2,23
1,96
3 39 41 29 18 14 3094500
94900
55100
1,43
1,62
1,08
4 39 42 31 24 12 2991200
95600
64600
1,25
`1,15
0,86
Rata-
rata37,75
38,5
30,75
23,5
20,25 32
101650
98900
71150
1,39
1,59
1,17
Sumber Data Rekapan
Tabel 5.2 Hasil Pengamatan Tinggi dan Jumlah daunMingg
uTinggi Tanaman
(cm) Jumlah Daun
Ke-50X40
25X40
Paranet
50X40
25X40
Paranet
1 12,5 10 5,5 3 3 2
2 36 37,5 35,9 6 7 5
3 67 63 60 8 7 7
4 98 93 87 14 12 11
Sumber Data Rekapan
67
1 2 3 40
20
40
60
80
100
120Tinggi Tanaman (cm) 50X40Tinggi Tanaman (cm) 25X40Tinggi Tanaman (cm) Paranet
Gambar 5.1 Grafik Pertumbuhan Tinggi Tanaman Pada Tiga
Perlakuan Tanaman Jagung
1 2 3 40246810121416
Jumlah Daun 50X40Jumlah Daun 25X40Jumlah Daun Paranet
Gambar 5.2 Grafik Jumlah Daun Pada Tiga Perlakuan
Tanaman Jagung
68
E. PEMBAHASANBerdasarkan pengamatan unsur iklim mikro yang
telah dilakukan pada tiga perlakuan tanaman jagung di
Kebun Fakultas Pertanian UNS, Desa Sukosari,
Kecamatan Jumantono diperoleh Data Rekapan Unsur
Iklim Mikro Pada Tiga Perlakuan Tanaman Jagung.
Perlakuan yang pertama adalah tanaman jagung yang
ditanam pada petak tanam yang memiliki jarak tanam
50 x 40 cm. Perlakuan yang kedua adalah tanaman
jagung yang ditanam pada petak tanam yang memiliki
jarak tanam 25 x 40 cm, sedangkan yang terakhir
dilakukan penanaman jagung pada petak tanah yang
diberi paranet.
Pada pengamatan tanaman jagung yang ditanam pada
petak tanam dengan jarak 50 x 40 cm setelah diamati
suhunya, memiliki suhu rata-rata sekitar 37,750C.
Kelembaban udaranya rata–rata sekitar 23,5%, memiliki
intensitas radiasi rata –rata sebesar 101650 dan
kecepatan anginnya sebesar 1,39 m/s. Tanaman jagung
pada petak tanam yang ditanam dengan jarak 25 x 40 cm
memiliki suhu udara rata-rata sekitar 38,50C dan
kelembaban udaranya sekitar 20,5%. Memiliki
intensitas radiasi sebesar 98900 dan kecepatan
anginnya sekitar 01,59 m/s. Pada petak tanam yang
diberi paranet, diperoleh data suhu udara sekitar
30,750, memiliki kelembaban udara sekitar 32%,
69
memiliki intensitas radiasi sebesar 71150 dan
kecepatan anginnya sebesar 1,18 m/s..
Berdasarkan hasil pengamatan yang telah
dilakukan, diperoleh data rekapan tinggi tanaman dan
jumlah daun pada tiga perlakuan tanaman jagung.
Minggu pertama, tanaman jagung yang ditanam di petak
tanam dengan jarak 50 x 40 cm, tinggi tanamannya
sekitar 12,5 cm dan memiliki jumlah daun 3 helai.
Pada tanaman jagung yang ditanam di petak tanam
dengan jarak 25 x 40 cm, tinggi tanaman sekitar 10
cm dan jumlah daunnya 3 helai. Pada tanaman jagung
yang diberi paranet, tinggi tanaman kurang lebih 5,5
cm dan jumlah daunnya 2 helai.
Di minggu kedua, tanaman jagung dengan jarak
tanam 50 x 40 cm memiliki tinggi sekitar 36 cm dengan
jumlah daun sebanyak 6 helai. Pada petak pertanaman
yang diberi jarak tanam 25 x 40 cm tanaman jagung
memiliki tinggi 37,5 cm dan daunnya berjumlah 7
helai, sedangkan pada petak pertanaman yang diberi
paranet, tinggi tanamannnya sekitar 35,9 cm dengan
jumlah daun sebanyak 5 helai.
Di minggu ketiga, tanaman jagung yang ditanam di
petak tanam dengan jarak 50 x 40 cm, tinggi
tanamannya sekitar 67 cm dan memiliki jumlah daun 8
helai. Pada tanaman jagung yang ditanam di petak
tanam dengan jarak 25 x 40 cm, tinggi tanaman
sekitar 63 dan jumlah daunnya 7 helai. Pada tanaman
70
jagung yang diberi paranet, tinggi tanaman kurang
lebih 60 cm dan jumlah daunnya 7 helai.
Di minggu keempat, tanaman jagung dengan jarak
tanam 50 x 40 cm memiliki tinggi sekitar 98 cm dengan
jumlah daun sebanyak 14 helai. Pada petak pertanaman
yang diberi jarak tanam 25 x 40 cm tanaman jagung
memiliki tinggi 93cm dan daunnya berjumlah 12 helai,
sedangkan pada petak pertanaman yang diberi paranet,
tinggi tanamannnya sekitar 87 cm dengan jumlah daun
sebanyak 11 helai.
Dari pengamatan tersebut tanaman dapat tumbuh
dan berkembang dengan baik pada petak tanaman 50 x
40. Dari Data Rekapan Unsur Iklim Mikro Pada Tiga
Perlakuan Tanaman Jagung di peroleh grafik 5.1 yang
menunjukkan pertumbuhan tanaman jagung lebih pesat
pada perlkuan 50 x 40, sedagkan pada perlakuan
tanaman tidak tumbuh dengan maksimal dikarenakan
unsur suhu, kelembaban, intensitas radiasi serta
kecepatan angin yang mempengaruhi tanaman kurang
sesuai.
71
F. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
a. Tanaman jagung dengan berbeda perlakuan
seperti memberi jarak tanam 50 x 40, 25 x 40
dan diberi paranet memiliki suhu udara,
kelembaban, intensitas radiasi serta kecepatan
angin yang berbeda-beda.
b.Tanaman jagung dengan berbeda perlakuan,
ternyata memiliki pengaruh perbedaan di dalam
tinggi tanaman dan jumlah daun.
c.Perbandingkan tanaman yang diberi paranet
dengan tidak diberi paranet memiliki suhu,
intensitas radiasi, dan kecepatan angin yang
rendah daripada yang lain. Tetapi kelembaban
udaranya paling tinggi diantara tanaman yang
tidak diberi paranet.
d.Tanaman jagung cocok tumbuh dengan perlakuan
jarak tanam 50 x 40, karena denga suhu optimum
maka kelembaban yang diterima juga optimum
untuk pertumbuhan tanaman jagung. Karena jagung
memerlukan intensitas radiasi yang cukup serta
kecepatan angin yang optimum maka akan lebih
baik di tanam dengan perlakuan jarak tanam 50 x
40.
2. SaranPenambahan alat untuk pengukuran, sehingga
dapat dimanfaatkan oleh banyak kegiatan praktikum
72
dan tidak saling menunggu, karena dapat membuag
banyak waktu yang seharusnya optimal digunakan
untuk praktikum.
73
DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, A.G. 2003. Alam Sekitar dan Pembangunan. http://portal.kukum.edu.my. Diakses pada 26 November 2014
Noorhadi dan Sudadi. 2003. Kajian pemberian air danmulsa terhadap iklim mikro pada tanaman cabaidi tanah entisol. Jurnal Ilmu Tanah danLingkungan 4 (1) : 41-49
Oktavia. 2009. Iklim Makro dan Mikro.<http://mengerjakantugas.blogspot.com/2009/02/iklim-makro-dan-iklim-mikro.html>. Diaksestanggal 29 November 2014
Villegasa, J.C., David D.B., Chris B.Z. and PatrickD.R. 2010. Seasonally Pulsed Heterogeneity inMicroclimate: Phenology and Cover Effects alongDeciduous Grassland–Forest Continuum. VadoseZone Journal 9 (3) : 537-547
Wisnubroto, S. 1981. Modifikasi Unsur Iklim UntukMendekati Persyaratan Optimal Bagi Tanaman.Fakultas Pertanian. UGM, Yogyakarta
VI. PEMATAH ANGIN
A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Kecepatan angin sangat berpengaruh terhadap
jau evapotranspirasi. Lahan yang berada di
wilayah yang rata-rata kecepatan anginnya besar,
perlu diberi pematah angin. Pematah angin adalah
bahan yang dipasang di lingkungan pertanaman,
bisa berupa pagar tanaman atau pagar kayu/bambu.
Penggunaan pematah angin dapat mengurangi
kecepatan angin di dalam pertanaman sehingga bisa
mengurangi laju evapotranspirasi.
2. Tujuan Praktikum
Acara praktikum pematah angin ini bertujuan
untuk mengetahui pengaruh penggunaan pematah
angin (windbreaker, shelterbelt) terhadap kecepatan angin
di dalam pertanaman
3. Waktu dan Tempat Praktikum
Acara pengaruh penggunaan pematah angin ini
dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 1 November
2014. Bertempat di kebun Fakultas Pertanian UNS,
desa Sukosari, kecamatan Jumantono, kabupaten
Karanganyar.
B. TINJAUAN PUSTAKA
68
69
Angin merupakan udara yang bergerak mengikuti
tinggi rendahnya tekanan udara. Alat penngukur
kecepatan angin adalah anemometer. Alat ini
diletakkan pada suatu tempat yang terbuka dan
selanjutnya karena embusan angin, alat ini akan
nenunjukkan arah angin dan kecepatannya
(Munawir et al 2006).
Dalam klimatologi angin diamati dalam kecepatan
dan arahnya. Kecepatan angin adalah jarak tempuh
massa udara yang bergerak tersebut dalam waktu
tertentu; jadi satuannya adalah jarak per waktu
seperti m per detik, km per jam.sedang arah angin
merupakan arah datangnya angin. (Syamsul 2008).
Angin secara tidak langsung mempunyai efek
penting pada produksi tanaman pangan. Energi angin
merupakan perantara dalam penyebaran tepung sari
pada penyerbukan alamiah, tetapi angin juda dapat
menyebarkan benih rumput liar dan melakukan
penyerbuka silang yang tidak diinginkan. Angin yang
terlalu kencang juga akan menggangu penyerbukan oleh
serangga.Angin dapat membantu dalam menyediakan
karbon dioksida yang membantu pertumbuhan tanaman,
selain itu juga mempengaruhi suhu dan kelembaban
tanah. Namun pada saat musim kemarau di beberapa
daerah di Indonesia bertiup angan fohn yang dapat
merusak karena bersifat kering dan panas. Pada siang
hari didaerah sekitar pantai, angin laut dapat
70
menyebabkan masalah karena angin ini membawa butiran
garam yang dapat merusak daun (Rahman 2013).
Angin yang tidak menguntungkan bagi pertanian
adalah angin fohn, karena dapat melayukan tanaman.
Angin fohn terjadi karena udara yang mengandung uap
air membentur pengunungan atau gunung yang tinggi,
sehingga naik. Makin ke atas, suhu makin dingin dan
terjadilah kondensasi yang selanjutnya terbentuk
titik-titik air. Titik-titik air itu kemudian jatuh
sebagai hujan sebelum mencapai puncak pada lereng
pertama. Angin terus bergerak menuju puncak,
kemudian jatuh pada lereng berikutnya sampai
kelembah. Karena sudah menjatuhkan hujan maka angin
yang menuruni lereng ini bersifat kering. Akibat
cepatnya gerakan menuruni lereng, angin menjadi
pasang sehingga angin fohn memiliki sifat menurun,
kering, dan panas (Wahyuningsih 2004).
Angin hampir tidak bisa dikendalikan. Perlu
adanya suatu pengelolaan lingkungan karena adanya
pengaruh angin yang sangat komplek ini. Salah satu
upaya yang dapat dilakukan yaitu menghindari adanya
pengaruh yang tidak dikehendaki misalnya penanaman
tanaman sejenis agar tidak terjadi penyerbukan
silang. Namun jika permasalahan penyebaran patogen
maka usaha yang dapat dilakukan yaitu pengendalian
sedini mungkin agar mengurangi jumlah patogen yang
dapat disebarkan oleh angin. Selain itu dapat pula
71
menggunakan tanaman pematah angin agar laju dan arah
angin dapat sedikit dikendalikan seperti menanam
pohon penahan angin yang dapat menjamin perlindungan
sejauh 15 – 20 kali tinggi pohon pelindung. Misalnya
tinggi pohon 10 meter, tanaman sejauh 150 – 200
meter dapat dilindungi sehingga memperlambat
kecepatan angin. Dengan adanya pematah angin maka
laju dan arah angin menuju pertanaman dapat sedikit
ditekan sehingga penyebaran patogen akan lebih kecil
(Okta 2013).
C. ALAT, BAHAN DAN CARA KERJA
1. Alat
a. Anemometer
b. Pematah angin
c. Alat tulis
2. Bahan
a. Tanaman jagung
3. Cara kerja
a. Menyiapkan 4 petak tanam
b. Menanam jagung manis pada ke 4 petak tersebut,
dengan jarak 50 cm x 40 cm
c. Dua dari 4 petak itu diperlukan tanpa pematah
angin
d. Dua petak yang lain diberi pematah angin
terbuat dari bambu pada tiga sisi luarnya
e. Melakukan pengamatan kecepatan angin pada ke 4
petak pertanaman jagung manis, pada sebelah
73
D. HASIL PENGAMATAN
Tabel 6.1 Hasil Pengamatan Tinggi dan Jumlah Daun pada Pematah Angin
Mingg
u Ke-
Kecepatan Angin
(m/s)
Tinggi Tanaman
Rata-rata (cm)
Jumlah Daun
Rata-rata
Pematah
Angin
Tanpa
Pematah
Pemat
ah
Angin
Tanpa
Pematah
Pematah
Angin
Tanpa
Pematah
1 0,6 0,55 11,5 10,8 3 3
2 1,48 1,38 38,5 38 6 6
3 0,92 0,63 71 68,1 8 10
4 1,08 0,18 92 96 14 13
Sumber Data Rekapan
1 2 3 4020406080100120 TINGGI
TANAMAN RATA-RATA PEMATAH ANGINTINGGI TANAMAN RATA-RATA TANPA PEMATAH
Gambar 6.1 Grafik Tinggi Tanaman Tanpa Pematah Angin dan Dengan Pematah Angin
1 2 3 40
5
10
15 JUMLAH DAUN RATA-RATA PEMATAH ANGINJUMLAH DAUN RATA-RATA TANPA PEMATAH
75
E. PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil pengamatan yang telah
dilakukan, diperoleh data rekapan tinggi tanaman
dan jumlah daun perlakuan tanpa pematah angin,
Perlakuan yang pertama adalah tanaman jagung yang
ditanam pada petak tanam yang diberi pematah
angin. Perlakuan yang kedua adalah tanaman jagung
yang ditanam pada petak tanam yang tidak diberi
pematah angin.
Pada perlakuan tanaman jagung yang ditanam
pada petak tanam yang diberi pematah angin di
minggu pertama, diperoleh kecepatan angin 0,6
m/s. Diperoleh tinggi tanaman 11,5 cm serta
dengan jumlah daun 3. Sedangkan pada perlakuan
tanaman jagung yang ditanam pada petak tanam yang
tidak diberi pematah angin di minggu pertama,
diperoleh kecepatan angin 0,55 m/s. Diperoleh
tinggi tanaman 10,8 cm serta dengan jumlah daun
3.
Pada perlakuan tanaman jagung yang ditanam
pada petak tanam yang diberi pematah angin di
minggu kedua, diperoleh kecepatan angin 1,48 m/s.
Diperoleh tinggi tanaman 38,5 cm serta dengan
jumlah daun 6. Sedangkan pada perlakuan tanaman
jagung yang ditanam pada petak tanam yang tidak
diberi pematah angin di minggu pertama, diperoleh
kecepatan angin 1,38 m/s. Diperoleh tinggi
76
tanaman 38 cm serta dengan jumlah daun 6. Pada
perlakuan tanaman jagung yang ditanam pada petak
tanam yang diberi pematah angin di minggu kedua,
diperoleh kecepatan angin 0,92 m/s. Diperoleh
tinggi tanaman 71 cm serta dengan jumlah daun 8.
Sedangkan pada perlakuan tanaman jagung yang
ditanam pada petak tanam yang tidak diberi
pematah angin di minggu pertama, diperoleh
kecepatan angin 0,63 m/s. Diperoleh tinggi
tanaman 68,1 cm serta dengan jumlah daun 10.
Pada perlakuan tanaman jagung yang ditanam
pada petak tanam yang diberi pematah angin di
minggu kedua, diperoleh kecepatan angin 1,08 m/s.
Diperoleh tinggi tanaman 92 cm serta dengan
jumlah daun 14. Sedangkan pada perlakuan tanaman
jagung yang ditanam pada petak tanam yang tidak
diberi pematah angin di minggu pertama, diperoleh
kecepatan angin 0,18 m/s. Diperoleh tinggi
tanaman 98 cm serta dengan jumlah daun 16.
Data Rekapan Tinggi Tanaman dan Jumlah Daun
Perlakuan Tanpa Pematah Angin dan Dengan Pematah
Angin didapatkan Grafik 6.1 yang menunjukkan
bahwa tanaman lebih tinggi pertumbuhannya tanpa
adanya pematah angin sedangkan pada grafik 6.2
didapatkan bahwa tanaman lebih banyak tumbuh daun
dengan adanya pematah angin. Pematah angin dapat
mempengaruhi pertumbuhan tanaman karena dengan
77
angin yang besar tanaman akan terganggu
pertumbuhannya. Apabila diberi pematah angin maka
laju kecepatan angin yang masuk pada petak
pertanaman akan terkontrol.
F. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
a. Tanaman jagung dengan perlakuan diberi pematah
angin pertumbuhan tinggi tanaman akan lebih
rendah daripada tanaman yang tidak diberi
pematah angin.
b. Tanaman jagung dengan perlakuan diberi pematah
angin maka pertumbuhan jumlah daunnya akan
lebih banyak daripada tanaman yang tidak diberi
pematah angin.
c. Rata-rata kecepatan angin yang masuk pada
pertanaman dengan diberi pematah angin lebih
besar daripada tanaman tanpa pematah.
2. Saran
Sebaiknya data yang diberikan pada praktikan
lebih diperhatikan lagi, dikarenakan data yang
diberikan tidak sinkron dengan kenyataan yang
terjadi di lapangan. Selain itu apabila di
sinkronkan dengan teori yang diperoleh, tidak
sesuai. Diharapkan co-asisten lebih teliti dalam
merekap data, karena data yang diterima akan
berpengaruh banyak terhadap laporan praktikan.
79
DAFTAR PUSTAKA
Munawir. 2006. Cakrawala Geografi. Yogyakarta: Yudistira
Okta Wiwijaya. 2013 pengaruh-angin-terhadap-tanaman.
Rafi’i, Suryatna. 1995. Meteorologi Dan Klimatologi. Bandung:
Angkasa
Wahyuningsih, Utami. 2004. Geografi. Pabelan, Jakarta.
VII. INTENSITAS RADIASI DI DALAM PERTANAMAN JAGUNG
A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Cahaya matahari adalah sumber energi utama
bagi kehidupan seluruh makhluk hidup di dunia.
Bagi manusia dan hewan cahaya matahari adalah
penerang dunia ini. Selain itu bagi tumbuhan
khususnya yang berklorofil cahaya matahari sangat
menentukan proses fotosintesis. Fotosintesis
adalah proses dasar pada tumbuhan untuk
menghasilkan makanan.Makanan yang dihasilkan akan
menentukan ketersediaan energi untuk pertumbuhan
dan perkembangan tumbuhan. Cahaya dibutuhkan oleh
tanaman mulai dari proses perkecambahan biji
sampai tanaman dewasa. Dengan demikian cahaya
dapat menjadi faktor pembatas utama di dalam semua
ekosistem.
Merupakan faktor lingkungan yang sangat
penting sebagai sumber energi utama bagi
ekosistem. Bagi tumbuhan khususnya yang
berklorofil cahaya matahari sangat berperan dalam
proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses
dasar pada tumbuhan untuk menghasilkan makanan.
Makanan yang dihasilkan akan menentukan
ketersediaan energi untuk pertumbuhan dan
perkembangan tumbuhan.
74
75
Intensitas cahaya atau kandungan energi
merupakan aspek cahaya terpenting sebagai faktor
lingkungan, karena berperan sebagai tenaga
pengendali utama dari ekosistem. Intensitas cahaya
ini sangat bervariasi baik dalam ruang/ spasial
maupun dalam waktu atau temporal.
Intensitas cahaya terbesar terjadi di daerah
tropika, terutama daerah kering (zona arid),
sedikit cahaya yang direfleksikan oleh awan. Di
daerah garis lintang rendah, cahaya matahari
menembus atmosfer dan membentuk sudut yang besar
dengan permukaan bumi. Sehingga lapisan atmosfer
yang tembus berada dalam ketebalan minimum.
75
2. Tujuan Praktium
Acara praktikum intensitas radiasi di dalam
pertanaman jagung bertujuan untuk mengetahui
pengaruh penggunaan reflektor dan naungan di dalam
pertanaman terhadap pertumbuhan tanaman jagung
yang manis.
3. Waktu dan Tempat Praktikum
Acara pengaruh penggunaan pematah angin ini
dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 1 November
2014. Bertempat di kebun Fakultas Pertanian UNS,
desa Sukosari, kecamatan Jumantono, kabupaten
Karanganyar.
B. TINJAUAN PUSTAKA
Cahaya matahari adalah sumber energi utama bagi
kehidupan seluruh makhluk hidup didunia. Bagi
tumbuhan khususnya yang berklorofil, cahaya matahari
sangat menentukan proses fotosintesis. Fotosintesis
adalah proses dasar pada tumbuhan untuk menghasilkan
makanan. Makanan yang dihasilkan akan menentukan
ketersediaan energi untuk pertumbuhan dan
perkembangan tumbuhan (Sulistyono 2005).
Matahari merupakan sumber energi terbesar di
alam semesta. Energi matahari diradiasikan kesegala
arah dan hanya sebagian kecil saya yang diterima
oleh bumi. Energi matahari yang dipancarkan ke bumi
75
76
berupa energi radiasi. Disebut radiasi dikarenakan
aliran energi matahari menuju ke bumi tidak
membutuhkan medium untuk mentransmisikannya. Energi
matahari yang jatuh ke permukaan bumi berbentuk
gelombang elektromagentik yang menjalar dengan
kecepatan cahaya. Panjang gelombang radiasi matahari
sangat pendek dan biasanya dinyatakan dalam mikron
(Usman 2004).
Cahaya matahari mempengaruhi ekosistem secara
global karena matahari menentukan suhu. Cahaya
matahari juga merupakan unsur vital yang dibutuhkan
oleh tumbuhan sebagai produsen untuk
berfotosintesis. Cahaya Optimal bagi Tumbuhan
Kebutuhan minimum cahaya untuk proses pertumbuhan
terpenuhi bila cahaya melebihi titik kompensasinya
(Wirakusumah 2003).
Pada kegiatan budaya pertanian, pengaruh unsur
cahaya menjadi perhatian serius. Hal tersebut
dikarenakan hampir semua objek agronomi berupa
tanaman hijau yang memiliki kegiatan fotosintesa.
Penerapan energi pelengkap dalam bentuk kerja
manusia dan hewan, bahan bakar, mesin, alat-alat
pertanian, pupuk, dan, obat-obatan tidak lain adalah
sebagai usaha untuk meningkatkan proses konversi
energi matahari ke dalam bentuk produk tanaman.
Tidak semua energi cahaya matahari dapat diabsorpsi
oleh tanaman. Hanya cahaya tampak saja yang dapat
77
berpengaruh pada tanaman dalam kegiatan
fotosintesisnya. Cahaya itu disebut dengan PAR
(Photosynthetic Activity Radiation) dan mempunyai
panjang gelombang 400 mili mikronsampai 750 mili
mikron. Tanaman juga memberikan respon yang berbeda
terhadap tingkatan pengaruh cahaya yang dibagi
menjadi tiga yaitu, intensitas cahaya, kualitas
cahaya, dan lamanya penyinaran
(Ayla 2011).
Sebagian besar tanaman dari daerah sedang
adalah fotoperiodik. Namun demikian, di daerah
ekuator, panjang siang hari pada setiap bulan
menunjukkan perbedaan yang kecil sehingga pengaruh
kuantitas atau lamanya penyinaran matahari dalam
satu hari tidak mempengaruhi pertumbuhandan
perkembangan tanaman secara signifikan. Respon
fotoperiodik memungkinkan tanaman untuk mengatur
waktu bagi pertumbuhan vegetatif dan pertumbuhan
untuk membentuk bunga agar tetap tegar menghadapi
perubahan musim di dalam lingkungannya. Bila satu
tanaman dipindahkan ke daerah dengan garis lintang
berbeda, maka akan menghentikan fasenya dan tanaman
tersebut dapat mati, misalnya karena berusaha tumbuh
secara vegetatif pada musim dingin atau musim semi
(Handoko 2002).
Kekurangan cahaya matahari akan mengganggu
proses fotosintesis dan pertumbuhan, meskipun
78
kebutuhan cahaya tergantung pada jenis tumbuhan.
Selain itu, kekurangan cahaya saat perkembangan
berlangsung akan menimbulkan gejala etiolasi, dimana
batang kecambah akan tumbuh lebih cepat namun lemah
dan daunnya berukuran kecil, tipis dan berwarna
pucat (tidak hijau). Gejala etiolasi tersebut
disebabkan oleh kurangnya cahaya atau tanaman berada
di tempat yang gelap. Cahaya juga dapat bersifat
sebagai penghambat (inhibitor) pada proses
pertumbuhan, hal ini terjadi karena dapat memacu
difusi auksin ke bagian yang tidak terkena cahaya
(Usman 2004).
C. ALAT DAN CARA KERJA
1. Alat
a. Nauangan paranet
b. Reflektor berupa plastik warna perak hitam
c. Alat tulis
2. Bahan
a. Tanaman jagung
b. Sinar matahari
3. Cara Kerja
a. Menyiapkan 3 petak tanam
b. Menanan jagung manis pada ke petak tersebut,
dengan jarak tanam 50 cm x 40 cm
c. Satu petak pertanaman diperlukan tanpa naungan
dan tanpa reflektor
d. Satu petak yang lain diberi nauangan paranet
79
e. Satu petak lagi dipasang reflektor berupa
plastik warna perak hitam (warna perak di
bagian atas)
f. Melakukan pengamatan intensitas radiasi di
dalam pertanaman pada ketiga petak tersebut.
80
D. HASIL PENGAMATAN
Tabel 7.1 Hasil Pengamatan Data Curah HujanMinggu Intensitas Radiasi
Tinggi Tanaman(cm) Jumlah Daun
ke-50X40
Reflektor
Paranet
50X40
Reflektor
Paranet
50X40
Reflektor
Paranet
187900
109420
49100 11,5 9 5,5 3 2 3
2104800 98700
72200 31 30 28,1 5 7 5
397000 86400
50700 66 71 62 8 10 7
495600
104200
62900 84 96 80 12 13 10
Data Sumber Rekapan
1 2 3 40
20
40
60
80
100
120
Tinggi Tanaman (cm) 50X40Tinggi Tanaman (cm) ReflektorTinggi Tanaman (cm) Paranet
Gambar 7.1 Grafik Tinggi Tanaman Perlakuan
Intensitas Radiasi Matahari
81
1 2 3 40
2
4
6
8
10
12
14
Jumlah Daun 50X40Jumlah Daun ReflektorJumlah Daun Paranet
Gambar 7.2 Grafik Jumlah Daun Perlakuan Intensitas
Radiasi Matahari
82
E. PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil pengamatan yang telah
dilakukan, diperoleh Data Rekapan Tinggi Tanaman dan
Jumlah Daun Pada Perlakuan Intensitas Radiasi
Matahari. Perlakuan yang pertama adalah tanaman
jagung yang ditanam pada petak tanam yang memiliki
jarak tanam 50 x 40 cm. Perlakuan yang kedua adalah
tanaman jagung yang ditanam pada petak tanam yang
diberi reflektor, sedangkan yang terakhir dilakukan
penanaman jagung pada petak tanah yang diberi
paranet.
Pada pengamatan minggu pertama, tanaman jagung
yang ditanam pada petak tanam dengan jarak 50 x 40cm
setelah diamati suhunya, memiliki intensitas radiasi
sebesar 87900, tinggi tanaman 11,5cm, dan jumlah
daun 3 helai. Tanaman jagung pada petak tanam yang
diberi reflektor memiliki intensitas radiasi sebesar
109420, memiliki tinggi tanaman 9 dan jumlah daun 2
helai. Pada petak tanam yang diberi paranet,
diperoleh data intensitas radiasi sebesar 49100,
tinggi tanaman 5,5 dan jumlah daun 3 helai.
Pada pengamatan minggu kedua, tanaman jagung yang
ditanam pada petak tanam dengan jarak 50 x 40 cm
setelah diamati suhunya, memiliki intensitas radiasi
sebesar 104800, tinggi tanaman 31 cm, dan jumlah
daun 5 helai. Tanaman jagung pada petak tanam yang
diberi reflektor memiliki intensitas radiasi sebesar
83
98700, memiliki tinggi tanaman 30 cm dan jumlah daun
7 helai. Pada petak tanam yang diberi paranet,
diperoleh data intensitas radiasi sebesar 72200,
tinggi tanaman 28,1 dan jumlah daun 5 helai.
Pada pengamatan minggu ketiga, tanaman jagung
yang ditanam pada petak tanam dengan jarak 50 x 40cm
setelah diamati suhunya, memiliki intensitas radiasi
sebesar 97000, tinggi tanaman 66 cm, dan jumlah daun
8 helai. Tanaman jagung pada petak tanam yang
diberi reflektor memiliki intensitas radiasi sebesar
86400, memiliki tinggi tanaman 71 cm dan jumlah daun
10 helai. Pada petak tanam yang diberi paranet,
diperoleh data intensitas radiasi sebesar 50700,
tinggi tanaman 62 cm dan jumlah daun 7 helai.
Pada pengamatan minggu keempat, tanaman jagung
yang ditanam pada petak tanam dengan jarak 50 x 40cm
setelah diamati suhunya, memiliki intensitas radiasi
sebesar 95600, tinggi tanaman 84cm, dan jumlah daun
12 helai. Tanaman jagung pada petak tanam yang
diberi reflektor memiliki intensitas radiasi sebesar
104200, memiliki tinggi tanaman 96 cm dan jumlah
daun 13 helai. Pada petak tanam yang diberi paranet,
diperoleh data intensitas radiasi sebesar 62900,
tinggi tanaman 80 cm dan jumlah daun 10 helai.
Dari Data Rekapan Tinggi Tanaman dan Jumlah Daun
Pada Perlakuan Intensitas Radiasi Matahari
didapatkan rata-rata kecepatan angin terbesar
84
terdapat pada perlakuan tanaman dengan menggunakan
reflektor, karena radiasi yang datang ke bumi di
pantulkan melalui reflektor agar radiasi yang datang
dapat diserap lebih banyak oleh tanaman. Namun
tinggi tanaman dan jumlah daun tumbuh pesat pada
tanaman dengan perlakuan jarak tanam 50 x 40. Dari
grafik 7.1 dan 7.2 dapat terlihat bahwa pada
perlakuan 50 x 40 tanaman tumbuh lebih pesat
daripada tanaman dengan perlakuan dengan paranet
ataupun dengan reflektor. Karena apabila diberi
paranet maka tanaman secara tidak langsung akan
dinaungi oleh paranet sehingga intensitas radiasi
yang diterima taaman tidak sebesar dengan perlakuan
tanpa paranet.
85
F. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
a. Tanaman jagung dengan perlakuan jarak tanam 50
x 40 memperoleh intensitas radiasi sebesar
87900
b. Tanaman jagung dengan perlakuan diberi
reflektor memperoleh intensitas radiasi sebesar
109420
c. Tanaman jagung dengan perlakuan diberi paranet
memperoleh intensitas radiasi sebesar 49100
d. Tanaman dengan perlakuan diberi reflektor
memperoleh intensitas radiasi lebih besar
dibandingkan dengan perlakuan jarak tanam 50 x
40 atau perlakuan denga diberi paranet.
e. Tinggi tanaman dengan perlakuan jarak tanam 50
x 40 lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan
diberi reflektor atau dengan diberi paranet.
f. Jumlah daun tanaman dengan perlakuan jarak
tanam 50 x 40 lebih tinggi dibandingkan dengan
perlakuan diberi reflektor atau dengan diberi
paranet.
2. Saran
Sebaiknya data yang diberikan pada praktikan
lebih diperhatikan lagi, dikarenakan data yang
diberikan tidak sinkron dengan kenyataan yang
terjadi di lapangan. Selain itu apabila di
sinkronkan dengan teori yang diperoleh, tidak
86
sesuai. Diharapkan co-asisten lebih teliti dalam
merekap data, karena data yang diterima akan
berpengaruh banyak terhadap laporan praktikan.
87
DAFTAR PUSTAKA
Wirakusumah, S. 2003. Dasar-dasar Ekologi Bagi Populasi dan Komunitas. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia
Ayla 2011. Faktor-Faktor Lingkungan dan PembangunanHutan.http://www.silvikultur.com/faktor_lingkungan_pembangunan_hutan_ tanaman.htm. Diakses pada 1 Desember 2013.
Handoko 2002. Pendugaan Hasil Menggunakan Indeks Iklim Di dalam Kapita Selekta dalam Agroklimatologi. Jakarta:Dirjen-Dikti Depdikbud.
Kusuma, Yuriadi 2010. Modul 1 Sistem PengkondisianTeori Dasar. pksm.mercubuana.ac.id/new/.../files.../13039-1-325714992571.doc. Diakses pada 2 Desember 2013.
Usman 2004. Pemanfaatan Cahaya Matahari oleh Tumbuhan. Jurnal Natur Indonesia 6(2): 91-98
82
VIII. KLASIFIKASI IKLIM
A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Unsur-unsur iklim yang menunjukan pola
keragaman yang jelas merupakan dasar dalam
melakukan klasifikasi iklim. Unsur iklim yang
sering dipakai adalah suhu dan curah hujan
(presipitasi). Klasifikasi iklim umumnya sangat
spesifik yang didasarkan atas tujuan
penggunaannya, misalnya untuk pertanian,
penerbangan atau kelautan. Pengklasifikasian
iklim yang spesifik tetap menggunakan data unsur
iklim sebagai landasannya, tetapi hanya memilih
data unsur-unsur iklim yang berhubungan dan
secara langsung mempengaruhi aktivitas atau objek
dalam bidang-bidang tersebut ). Hujan merupakan
unsur fisik lingkungan yang paling beragam baik
menurut waktu maupun tempat dan hujan juga
merupakan faktor penentu serta faktor pembatas
bagi kegiatan pertanian secara umum, oleh karena
itu klasifikasi iklim untuk wilayah Indonesia
(Asia Tenggara umumnya) seluruhnya dikembangkan
dengan menggunakan curah hujan sebagai kriteria
utama
Di Indonesia yang sebagian besar penduduknya
masyarakat agraris yang bergerak di sektor
pertanian, sifat-sifat iklim seperti suhu, curah
82
83
hujan, dan musim sangat berpengaruh terhadap
kehidupannya. Faktor-faktor iklim seperti cuaca
dan iklim benar-benar dipertimbangkan dalam
mengemangkan pertanian. Kondisi suhu, curah hujan
dan pola musim sangat menentukan kecocokan dan
optimalisasi pembudidayaan tanaman pertanian.
Misalnya, padi sangat cocok dibudidayakan di
daerah yang bersuhu udara panas dengan curah
hujan yang cukup tinggi. Tanaman hortikultura
seperti sayur-sayuran dan buah-buahan cocok
dibudidayakan di daerah sedang sampai sejuk
dengan intensitas curah hujan tidak setinggi pada
tanaman padi
2. Tujuan Praktikum
Acara klasifikasi iklim ini dilaksanakan
dengan tujuan mahasiswa dapat mengklasifikasikan
iklim berdasarkan data curah hujan selama 10
tahun.
3. Waktu dan Tempat Praktikum
Praktikum agroklimatologi acara klasifikasi
iklim ini dilaksanakan pada tanggal 27 November
2012 bertempat di Argobudoyo Fakultas Pertanian
Univeritas Sebelas Maret Surakarta.
B. TINJAUAN PUSTAKA
Klasifikasi iklim yang dilakukan oleh Oldeman
didasarkan kepada jumlah kebutuhan air oleh tanaman,
84
terutama pada tanaman padi. Penyusunan tipe iklimnya
berdasarkan jumlah bulan basah yang berlansung
secara berturut-turut. Lamanya periode pertumbuhan
padi terutama ditentukan oleh jenis/varietas yang
digunakan, sehingga periode 5 bulan basah berurutan
dalan satu tahun dipandang optimal untuk satu kali
tanam. Jika lebih dari 9 bulan basah maka petani
dapat melakukan 2 kali masa tanam. Jika kurang dari
3 bulan basah berurutan, maka tidak dapat
membudidayakan padi tanpa irigasi tambahan (Pramudia
2008).
Kejadian iklim ekstrim dapat meningkatkan
ketidakpastian hasil yang merugikan petani. Agar
hasil yang didapatkan secara ekonomis tetap
menguntungkan, petani perlu melakukan antisipasi
terhadap kemungkinan kejadian iklim ekstrim. Iklim
dapat berubah seiring kejadian buruk yang mampu
merubah unsur iklim itu sendiri (Surmaini. et al,
2006).
Sistem Klasifikasi Schmidt-Ferguson merupakan
sistem iklim yang sangat terkenal di Indonesia.
Penyusunan peta iklim menurut klasifikasi Schmidt-
Ferguson lebih banyak digunakan untuk iklim hutan.
Pengklasifikasian iklim menurut Schmidt-Ferguson ini
didasarkan pada nisbah bulan basah dan bulan kering
seperti kriteria bulan basah dan bulan kering
klsifikasi iklim Mohr (Irianto dkk 2000).
85
Oldeman et al (1980) mengungkapkan bahwa
kebutuhan air untuk tanaman padi adalah 150 mm per
bulan sedangkan untuk tanaman palawija adalah 70
mm/bulan, dengan asumsi bahwa peluang terjadinya
hujan yang sama adalah 75% maka untuk mencukupi
kebutuhan air tanaman padi 150 mm/bulan diperlukan
curah hujan sebesar 220 mm/bulan, sedangkan untuk
mencukupi kebutuhan air untuk tanaman palawija
diperlukan curah hujan sebesar 120 mm/bulan,
sehingga menurut Oldeman suatu bulan dikatakan bulan
basah apabila mempunyai curah hujan bulanan lebih
besar dari 200 mm dan dikatakan bulan kering apabila
curah hujan bulanan lebih kecil dari 100 mm. Lamanya
periode pertumbuhan padi terutama ditentukan oleh
jenis/varietas yang digunakan, sehingga periode 5
bulan basah berurutan dalan satu tahun dipandang
optimal untuk satu kali tanam. Jika lebih dari 9
bulan basah maka petani dapat melakukan 2 kali masa
tanam. Jika kurang dari 3 bulan basah berurutan,
maka tidak dapat membudidayakan padi tanpa irigasi
tambahan (Tjasyono 2004).
Oldeman (1975) menggunakan periode bulan basah
dan kering yang terjadi secara kontinyu selama
setahun untuk menentukan pola hujan. Kriteria bulan
basah ditentukan berdasarkan nilai ambang batas
ketersediaan air yang dianggap mampu memenuhi
kebutuhan air tanaman (crop water requirement). Oleh
86
karena itu, hasil klasifikasi metode Oldeman ini
disebut sebagai klasifikasi agroklimat karena selain
untuk menentukan pola hujan juga menggambarkan
potensi periode masa tanam (length of growing period)
terutama tanaman padi. Metode Oldeman dipilih untuk
digunakan di dalam studi ini, agar dampak perubahan
pola hujan terhadap periode masa tanam dapat
teridentifikasi (Runtunuwu dan Syahbuddin 2007).
87
C. HASIL PENGAMATAN
1. Klasifikasi Iklim menurut Schmidt-Fergusson
Sistem iklim ini sangat terkenal di
Indonesia. Penyusunan peta iklim menurut
klasifkasi Schmidt-Ferguson lebih banyak
digunakan untuk iklim hutan. Pengklasifikasian
iklim menurut Schmidt-Ferguson ini didasarkan
pada nisbah bulan basah dan bulan kering.
Pencarian rata-rata bulan kering atau bulan basah
dalam klasifikasi iklim Schmidt-Ferguson
dilakukan dengan membandingkan jumlah atau
frekuensi bulan kering atau bulan basah selama
tahun pengamatan dengan banyaknya tahun
pengamatan. Bulan lembab dalam penggolongan ini
tidak dihitung. Persamaan yang dikemukakan
Schmidt-Ferguson adalah:
Q=Rata−rata Bulan KeringRata−rata Bulan Basah
×100%
Tabel 8.1 Klasifikasi iklim menurut Schmidt-Ferguson:
88
2. Klasifikasi
Iklim menurut
Oldeman
Klasifikasi Iklim yang dilakukan oleh Oldeman
didasarkan kepada jumlah kebutuhan air oleh
tanaman. Penyusunan tipe iklimnya berdasarkan
jumlah bulan basah yang berlangsung secara
berturut-turut. Menurut Oldeman suatu bulan
dikatakan bulan basah (BB) apabila mempunyai
curah hujan bulanan lebih besar dari 200 mm dan
dikatakan bulan kering (BK) apabila curah hujan
bulanan lebih kecil dari 100 mm.
Tipe Iklim Kriteria
A.(Sangat Basah)
B.(Basah)
C.(Agak Basah)
D.(Sedang)
E.(Agak Kering)
F.(Kering)
G.(Sangat Kering)
H.(Luar Biasa
Kering)
0 < Q <
0,143
0,143 < Q <
0,333
0,333 < Q <
0,600
0,600 < Q <
1,000
1,000 < Q <
1,670
1,670 < Q <
3,000
3,000 < Q <
7,000
7,000 < Q
89
Tabel 8. 2 Klasifikasi Iklim Menurut OldemanZona Kriteria
ABB > 9 kali berturut-
turut
BBB 7-9 kali berturut-
turut
CBB 5-6 kali berturut-
turut
DBB 3-4 kali berturut-
turut
EBB kurang dari 3
kali
Segitiga Oldman :
90
Tabel 8.2 Curah Hujan di Kecamatan Sidomukti selama 10 tahun
TahunBulan
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004 Total Rata-rata
Schmidt-ferguson
Oldeman
Januari 341 149 249 106 105 77 150 126 143 152 1598 159,8 BB BL
Februari 328 253 181 199 176 58 188 85 123 124 1715 171,5 BB BL
Maret 260 20 125 187 91 77 104 131 105 97 1197 119,7 BB BL
April 94 102 111 125 67 77 191 69 41 71 948 94,8 BL BK
Mei 54 25 73 102 20 38 34 0 37 43 426 42,6 BK BK
Juni 93 5 0 105 19 5 25 14 5 0 271 27,1 BK BK
Juli 13 38 7 115 8 7 8 0 0 38 234 23,4 BK BK
Agustus 0 49 0 34 7 13 0 0 0 0 103 10,3 BK BK
September 17 11 0 26 0 18 14 0 6 14 106 10,6 BK BK
Oktober 91 54 31 113 56 53 143 19 34 42 636 63,6 BL BK
91
November 339 158 78 67 82 94 74 116 61 122 1191 119,1 BB BL
Desember 156 74 158 89 56 24 34 0 121 193 905 90,5 BL BK
92
Iklim menurut Schmidt-Ferguson
Q=54
= 1,25Berarti, tipe iklim menrut Shmidt-Ferguson adalah
tipe iklim E yaitu agak kering karena Q = 1,25
dimana tipe E itu 1,000 < Q < 1,670.
Iklim menurut OldemanBulan basah yang berlangsung secara berturut-turut
ada 3 sehingga ternasuk kedalam Zona E = BB kurang
dari 3 kali.
D. PEMBAHASAN
Klasifikasi iklim memiliki tujuan menetapkan
pembagian ringkas jenis iklim ditinjau dari segi
unsur yang benar-benar aktif terutama presipitasi
dan suhu. Unsur lain seperti angin, sinar matahari,
atau perubahan tekanan ada kemungkinan merupakan
unsur aktif untuk tujuan khusus. Dasar-dasar
klasifikasi iklim diantaranya:
a. Unsur-unsur iklim yang menunjukan pola keragaman
yang jelas merupakan dasar dalam melakukan
klasifikasi iklim. Unsur iklim yang sering
dipakai adalah suhu dan curah hujan
(presipitasi).
93
b. Klasifikasi iklim umumnya sangat spesifik yang
didasarkan atas tujuan penggunaannya, misalnya
untuk pertanian, penerbangan atau kelautan.
c. Pengklasifikasian iklim yang spesifik tetap
menggunakan data unsur iklim sebagai landasannya,
tetapi hanya memilih data unsur-unsur iklim yang
berhubungan dan secara langsung mempengaruhi
aktivitas atau objek dalam bidang-bidang
tersebut.
Iklim dapat diartiakan sebagai berbagai macam
keadaan atmosfer (suhu, tekanan, kelembaban) yang
terjadi di suatu wilayah selama kurun waktu yang
panjang. Untuk dapat memahami cuaca dan iklim serta
persebarannya menurut ruang dan waktu diperlukan dasar
pengetahuan fisika atmosfer, pemahaman geografi serta
statistika dan matematika untuk menyederhakan kerumitan
proses-proses tersebut. Cuaca dan iklim dinyatakan dengan
susunan unsur-unsur cuaca dan iklim yang terdiri dari:
radiasi surya, lama penyinaran surya, suhu udara,
kelembapan udara, tekanan udara, kecepatan dan arah angin,
penutupan awan, presipitasi dan evaporasi/evapotranspirasi.
Berdasarkan hasil dari tabel dapat diketahui
bahwa curah hujan rata-rata Sidomukti tahun 1995-
2004 yang dihitung menggunakan sistem klasifikasi
Iklim Schmit-Ferguson adalah tipe E karena nilai Q=
1,25 yaitu kategori agak Kering. Samahalnya
perhitungan menurut system klasifikasi iklim Oldeman
termasuk iklim BB kurang dari 3 kali termasuk
kedalam zona E.
94
Jika Seorang petani di Sidomukti mempunyai lahan
seluas 1 ha dan ingin menanam kedelai (Glycine max).
Diketahui syarat tumbuh tanaman kedelai:
a.Menghendaki tanah yang cukup gembur, tekstur
lempung berpasir dan liat. Tanah hendaknya
mengandung cukup air tapi tidak sampai tergenang.
b.Menghendaki iklim dengan suhu relatif tinggi,
kelembaban rendah dan tumbuh baik pada ketinggian
0 – 400 m dpl
c.Curah hujan 1000 - 2000 mm/tahun
Menurut perhitungan Shmidth-Ferguson dan Oldemen
tanaman kedelai tidak cocok untuk dibudidayakan di
Kecamatan Sidomukti karena dari data curah hujan
yang diperoleh dalam 10 tahun ini menunjukkan bahwa
rata-rata curah hujan di daerah kecamatan Sidomukti
adalah 933 mm/tahun, sedangkan syarat untuk tumbuh
kedelai adalah jika curah hujan 1000-2000 mm/tahun.
Maka tanaman kedelai tidak cocok dibudidayakan di
Kecamatan Sidomukti.
Tanaman kedelai ini untuk menunjang pertumbuhan
dan mendapatkan produksi yang tinggi perlu dilakukan
modifikasi iklim. Modifikasi iklim yang dapat
dilakukan adalah dengan menggunakan mulsa di atas
permukaan tanah. Modifikasi ini dlakukan agar
transportasi yang terjadi tidak terlalu besar,
sehingga walaupun curah hujan di Kecamatan Sidomukti
rendah, kelembaban udara yang berpengaruh pada
96
E. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
a. Iklim dapat diartiakan sebagai berbagai
macam keadaan atmosfer (suhu, tekanan,
kelembaban) yang terjadi di suatu wilayah selama
kurun waktu yang panjang.
b. Klasifikasi Iklim berdasarkan perhitungan
curah hujan yang biasa digunakan adalah
Klasifikasi Iklim Oldeman dan klasifikasi iklim
menurut Schmidt-Ferguson.
c. Pengklasifikasian iklim menurut Schmidt-
Ferguson ini didasarkan pada nisbah bulan basah
dan bulan kering.
d. Klasifikasi iklim Oldeman didasarkan kepada
jumlah kebutuhan air oleh tanaman, terutama pada
tanaman padi.
e. Kecamatan Sidomukti tahun 1995-2004 yang
dihitung menggunakan sistem klasifikasi Iklim
Schmit-Ferguson adalah tipe E karena nilai Q=
1,25 % yaitu kategori agak kering. Samahalnya
dengan system klasifikasi iklim Oldeman termasuk
Zona E dengan BB kurang dari 3 kali.
2. Saran
Dalam praktikum selanjutnya diharapkan dalam
menjelaskan tata cara menghitung curah hujannya
lebih spesifik, karena klasifikasi iklim hubungannya
97
dengan pertanian erat kaitannya dengan penentuan
sistem pola tanam.
DAFTAR PUSTAKA
Irianto, Gatot., Le Istiqlal Amin, Elza Surmaini. 2000.Keragaman Iklim Sebagai Peluang Diversifikasi. PusatPenelitian Tanah dan Agroklimat.
Pramudia, A., Y. Koesmaryono, I. Las, T. June, I W.Astika, dan E. Runtunuwu. 2008.Penyusunan modelprediksi curah hujan dengan teknik analisisjaringan syaraf (neural network analysis) disentra produksi padi di Jawa Barat danBanten.Jurnal Tanah dan Iklim 27: 11-12.
Runtunuwu, E. dan H. Syahbuddin. 2007. Perubahan PolaCurah Hujan dan Dampaknya Terhadap Periode MasaTanam. Jurnal Tanah dan Iklim No. 26/2007. Bogor.
Surmaini, E., Boer, R., Siregar, H. 2006. PemanfaatanInformasi Iklim untuk Menunjang Usahatani TanamanPangan. Jurnal Tanah dan Iklim No. 24/2006. Bogor.
Tjasyono, Bayong. 2004. Klimatologi. IPB Press. Bandung