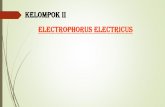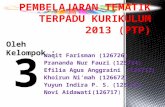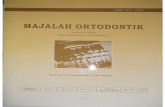KEDOKTERAN GIGI TERPADU - karya ilmiah universitas trisakti
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
10 -
download
0
Transcript of KEDOKTERAN GIGI TERPADU - karya ilmiah universitas trisakti
Scientific Journal in Integrated Dentistry
Januari 2019. Volume 05. No. 01
ISSN : 977 2407841 159
KEDOKTERAN GIGI TERPADU
Jurnal Ilmiah
Jurnal Ked.Gigi Terpadu
Vol. 5 No. 01 Hlm. 1-73 Januari 2019
ISSN 977 2407841 159
Jurnal Ilmiah
KEDOKTERAN GIGI TERPADU
Penasehat :
Prof.Dr.Tri Erri Astoeti A., drg., MKes (Dekan FKG USAKTI)
Penanggung Jawab:
Dr. Wita Anggraini, MBiomed., drg., PAK., SpPerio
Pemimpin Redaksi:
Enrita Dian Rahmadini, drg.Sp.KGA
Dewan Redaksi:
Caroline D. Marpaung, drg.Sp.Pros
Tri Putriany Agustin, drg.Sp.KGA
Arianne Dwimega, drg. Sp.KGA
Armelia Sari, drg..MBiomed
Goalbertus, drg.,MM
Mitra Bestari:
Prof.Dr. Boedi Oetomo R., drg., M.Biomed (Usakti)
Prof. Dr.Melanie H.Sadono,drg., M.Biomed (Usakti)
Prof.Dr. Bambang S.Trenggono, drg.,MBiomed (Usakti)
Prof. Dr. Lies ZubardiahM. Qosim, drg., Sp.Perio (Usakti)
Prof.Dr.F.Loes Djimahit S, drg., M.Kes (Usakti)
Prof. Dr. Tri Erri Astoeti, drg., M.Kes (Usakti)
Prof.Dr. E.Arlia Budiyanti,drg., SU (Usakti)
Prof.Dr. Suzan Elias, drg., Sp.Prost (Usakti)
Prof.Dr.S.S. Winanto, drg., Sp.KG (Usakti)
Prof. Anton Margo, drg., Sp.Pros (Usakti)
Prof. Janti Sudiono, drg., MDSc (Usakti)
Alamat Redaksi:
Bagian Kesehatan Gigi Anak
Fakultas Kedokteran Gigi-Universitas Trisakti
Jalan Kyai Tapa, Grogol, Jakarta 11440 Indonesia
Telepon: 021-5672731 ext. 1604
Email: [email protected]
Kata Pengantar
Pembaca yang budiman
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan
pertolongannya Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu dapat terbit di awal tahun 2019. Berkala
Jurnal ilmiah ini akan terbit setahun dua kali yaitu pada bulan Januari dan Juli. Di dalam volume
ini kami menyajikan artikel-artikel yang beragam dari berbagai bidang ilmu, yang meliputi:
Biologi Oral, Ilmu Anatomi, Mikrobiologi, Ilmu Bahan Kedokteran Gigi, Radiologi, Ilmu Bedah
Mulut, Ilmu Penyakit Mulut, Ortodonsia, Periodonsia, Prostodonsia dan Ilmu Konservasi Gigi.
Kami berharap sajian kali ini dapat memperkaya khasana Ilmu Kedokteran Gigi secara
terpadu. Redaksi berharap masukan serta dukungan para penulis dan pembaca demi
kelanggengan berkala ilmiah ini.
Salam Redaksi
Jurnal Ilmiah
KEDOKTERAN GIGI TERPADU
ISSN 977 2407841 159 Vol. 05, No. 01, Januari 2019
Daftar Isi
Penatalaksanaan Kasus Pencabutan Gigi Depan dengan Gigi Tiruan
Sebagian Lepasan Imidiat
(Laporan Kasus)
Andy Wirahadikusumah
1 – 5
Pengaruh Sikat dan Pasta Gigi Terhadap Kekasaran Permukaan Resin
Komposit Nanohibrida
(Laporan Penelitian) Deviyanti Pratiwi, Selvia Rizki Mulya
6 – 9
Pengaruh Bahan Bleaching Karbamid Peroksida 20% Dan 35% Terhadap
Kekerasan Resin Komposit Tipe Nano Hibrid
(Laporan Penelitian)
Dewi Liliany Margaretta, Reinaldo Sugianto
10 – 16
Regenerasi Tulang pada Kasus Abses Apikalis Kronis
(Laporan Kasus)
Elline
17 – 20
Hubungan Antara Gigi Berjejal Dan Gingivitis
(Laporan Penelitian)
Lies Zubardiah, Marilyn Octavia
21 – 27
Pertumbuhan Linier (stature) dan Tulang Dentofasial pada Penderita
Talasemia Beta Mayor
(Studi Pustaka)
Loes D Sjahruddin
28 – 32
Pentingnya Faktor Ergonomi dalam Penerapan Manajemen Keselamatan
dan Kesehatan Kerja Guna Pencegahan Nyeri Punggung Bawah pada
Dokter Gigi
(Studi Pustaka)
Mita Juliawati
33 – 40
Perawatan Ortodonti Paska Bedah Ortognati
(Tinjauan Pustaka)
Olivia Piona Sahelangi
41 – 45
Potensi Ekstrak Daun Dandang Gendis (Clinacanthus nutans) untuk
Mempercepat Penyembuhan Luka di Rongga Mulut
(Tinjauan Pustaka)
Moehamad Orliando Roeslan
46 – 52
Endokarditis Bakterialis pada Anak : Suatu Tinjauan Untuk Dokter Gigi
(Studi Pustaka)
Sri Ratna Laksmiastuti
53 – 58
Infeksi pada Dental Implan Serta Perawatannya
(Studi Pustaka)
Trijani Suwandi
59 – 65
Prevalensi Premature Loss Gigi Molar Kedua Sulung Dan Gambaran
Maloklusi. Kajian pada Pasien ortodonti RSGM Universitas Trisakti
tahun 2013– 2016
(Laporan Penelitian)
Yuniar Zen, Krisnadya Dewa Yanti
66 – 73
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 1-5
1
Penatalaksanaan Kasus Pencabutan Gigi Depan dengan Gigi Tiruan Sebagian Lepasan
Imidiat
(Laporan Kasus)
Andy Wirahadikusumah
Staf Pengajar Bagian Prostodontik Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti,
ABSTRACT
Background: Almost all physical changes or loss cause psychological trauma to the patient. For
instance, patient may experience low self-esteem, get easily annoyed, and angry. Similar condition
may occur in patients who lost their front teeth. To add to psychological trauma, problems in
mastication and phonetic function may also develop. Objective: To discuss immediate removable
denture treatment management as a treatment alternative in cases with an esthetic function needs.
Case Report and Management: Patient came with fracture and mobile front teeth. The treatment
plan is to extract the anterior teeth, but patient doesn’t want to undergo edentulous period because of
low self-esteem of meeting other people.Treatment alternative for patient who doesn’t want to
undergo edentulous period is by making an Imidiate Removable Partial Denture ( IRPD ). Imidiate
removable partial denture inserted directly on the same day after teeth extraction.
Conclusion : Imidiate Removable partial denture can be an alternative to replace conventional
removable partial denture in which case of patient doesn’t want to undergo edentulous period . This
denture can be made for patient who already use removable partial denture and patient who never
used it.
Key word: Imidiate removable partial denture, acrylic removable partial denture, edentulous period
PENDAHULUAN
Estetik dan fonetik merupakan masalah
utama yang harus dihadapi oleh pasien akibat
kehilangan gigi atau gigi gigi depannya. Untuk
mengatasi masalah ini dapat dibuatkan gigi
tiruan yang dipasang segera setelah gigi gigi
depan tersebut dicabut dan dikenal sebagai gigi
tiruan imidiat.
Suatu gigi tiruan imidiat adalah gigi tiruan
yang dibuat sebelum pencabutan gigi atau gigi
gigi asli dan dipasang segera setelah pencabutan
gigi tersebut. Pembuatan gigi tiruan imidiat ini
dapat dilakukan pada kasus-kasus dengan
pembuatan geligi tiruan cekat (bridge), gigi
tiruan lepasan penuh dan gigi tiruan sebagian
lepasan dan dapat dibuat baik untuk satu maupun
untuk kedua rahang. Pada kasus yang akan
dibuatkan gigi tiruan penuh imidiat pada rahang
atas dan bawah sebaiknya dilakukan bersamaan
untuk menghindari penyusunan gigi-gigi yang
mengikuti bidang oklusal gigi asli yang tersisa
dimana biasanya telah mengalami perubahan
yang merugikan. 1
Gigi tiruan lepasan imidiat dapat berfungsi
sebagai gigi tiruan sementara (transisional
denture) dimana setelah penyembuhan luka
pencabutan dibuatkan gigi tiruan yang baru,
sedangkan bila berfungsi sebagai gigi tiruan tetap
maka gigi tiruan imidiat tersebut perlu dilakukan
penyesuaian dan perbaikan sesuai dengan proses
penyembuhan luka pencabutan dengan
melakukan direct relining. 2
Gigi tiruan sebagian lepasan imidiat dapat
dibuat baik untuk gigi depan maupun untuk gigi
belakang , akan tetapi untuk gigi depan gigi gigi
tiruan ini lebih sering dibuat guna
menanggulangi trauma psikologis akibat
terganggunya estetik dan fonetik. Gigi tiruan
sebagian lepasan imidiat untuk gigi belakang
biasanya dibuat pada pasien yang membutuhkan
peningkatan fungsi mastikasi, misalnya pada
pasien dengan kelainan fungsi lambung dan gigi
tiruan jenis ini jarang dibuat. 2
TINJAUAN PUSTAKA
Kehilangan gigi depan dapat disebabkan
karena pencabutan gigi yang terpaksa dilakukan
untuk memperbaiki estetik pasien, misalnya pada
kasus protrusi gigi depan yang terlalu ekstrim
atau disebabkan akibat penyakit periodontal yang
biasanya disertai dengan terdapatnya karies pada
daerah servikal gigi atau bahkan pada permukaan
akar gigi. Untuk mengatasi masalah kehilangan
gigi tersebut biasanya dibuatkan gigi tiruan
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 1-5
2
imidiat yang dapat berupa gigi tiruan cekat
imidiat atau gigi tiruan lepasan imidiat. Gigi
tiruan lepasan imidiat dapat berupa gigi tiruan
sebagian lepasan bila masih terdapat beberapa
gigi posterior atau dapat berupa gigi tiruan penuh
imidiat bila gigi gigi posterior telah dicabut atau
pasien telah memakai gigitiruan sebagian lepasan
berujung bebas (free end denture).3
Perawatan dengan pembuatan gigi tiruan
imidiat ini sebaiknya diberikan untuk pasien
pasien dengan kondisi kesehatan umumnya baik,
berusia relatif muda, memperhatikan
keberhasilan mulut nya, pasien yang dapat
bekerja sama (kooperatif). 2,3
Ada 2 tipe/jenis dari gigi tiruan sebagian
lepasan imidiat gigi anterior yaitu: tanpa sayap
(dengan soket); dengan sayap sebagian atau
penuh. (Gambar.1.). Indikasi kedua jenis gigi
tiruan ini sangat dipengaruhi oleh tipe profil
wajah pasien atau hubungan antara rahang atas
dan rahang bawah dari pasien sedangkan gigi
tiruan sebagian lepasan imidiat dengan sayap
penuh dibuat untuk kasus pencabutan gigi
anterior dengan alveolektomi atau tanpa
alveolektomi. Hal hal yang penting yang perlu
dipertimbangkan dalam menentukan tipe gigi
tiruan sebagian lepasan imidiat adalah :
kedalaman gerong labial; tonus bibir; aktifitas
bibir; besar/derajat kelainan periodontal; bentuk
tulang alveolar; tindakan pembedahan
(alveolektomi). 2
Gambar.1. Tipe gigi tiruan sebagian lepasan imidiat
gigi anterior yaitu: a. tanpa sayap (dengan soket), b.
dengan sayap sebagian, c. dengan sayap penuh.2
Adapun indikasi khusus untuk gigi tiruan
lepasan imidiat (GTSI) gigi anterior tersebut
adalah:
1. GTSI gigi anterior tanpa sayap:
a. Terdapat daerah gerong dalam pada bagian
labial daerah tak bergigi.
b. Bentuk bibir yang pendek dan aktif
sehingga pemakaian sayap akan
mengganggu estetik.
c. Kasus yang membutuhkan tindakan bedah
yang minimalis.
2. GTSI gigi anterior dengan sayap sebagian
a. Terdapat gerong pada bagian labial daerah
tak bergigi
b. Sayap dibutuhkan sebagai splin setelah
tindakan bedah
3. GTSI gigi anterior dengan sayap penuh:
a. Terdapat sedikit gerong dalam pada bagian
labial linggir sisa.
b. Bentuk bibir yang panjang dan
aktivitasnya normal.
c. Kasus dengan kelainan periodontal,
dimana tulang pendukung sekitar gigi
yang akan dicabut, sudah banyak hilang.
Sedangkan kontraindikasi untuk gigi tiruan
lepasan imidiat (GTSI) gigi anterior adalah:
1. GTSI gigi anterior tanpa sayap:
a. Penderita dengan kelainan periodontal
disertai resorpsi tulang alveolar.
b. Kasus dengan bentuk tulang alveolar tak
beraturan
2. GTSI gigi anterior dengan sayap sebagian
a. Penderita dengan bibir hiperaktif, sehingga
penggunaan sayap akan menyebabkan
terlihatnya mukosa, sehingga member efek
estetik yang buruk
b. Keadaan sosial dan ekonomi pasien
kurang, padahal pembuatan gigi tiruan
semacam ini perlu koreksi, sehingga perlu
biaya tambahan.2
3. GTSI gigi anterior dengan sayap penuh:
a. Pasien dengan gerong dalam pada region
labial linggir sisa.
b. Pasien dengan profil protrusif, sehingga
adanya sayap memberi kesan mulut jadi
penuh.2
Seperti halnya perawatan dengan
pembuatan gigi tiruan konvensional, maka
perawatan dengan pembuatan gigi tiruan imidiat
juga mempunyai keuntungan antara lain: pasien
tidak merasakan periode tidak bergigi yang dapat
menimbulkan rasa malu/rendah diri karena tidak
merasakan adanya perubahan penampilan dan
bicara; gigi tiruan menjadi pelindung terhadap
luka pencabutan sehingga akan mengurangi rasa
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 1-5
3
sakit, pembengkakan dan perdarahan; adaptasi
terhadap gigi tiruan lebih baik karena pasien
langsung memakai gigi tiruan setelah pencabutan
gigi; pasien tidak perlu mempertahankan gigi
gigi yang telah mengalami kerusakan;
mempercepat terjadinya penyembuhan luka
bekas pencabutan. Sedangkan hal yang
merugikan dari perawatan dengan pembuatan
suatu gigi tiruan imidiat adalah: waktu perawatan
menjadi lebih panjang; memerlukan biaya yang
lebih besar karena biasanya memerlukan relining
atau rebasing; tidak dapat melakukan tahap
mencoba gigi tiruan malam untuk mengamati
segi estetik; indikasi terbatas; kecekatan tidak
dapat bertahan untuk waktu yang lama akibat
resorbsi alveolar setelah pencabutan.3,4
Beberapa hal yang perlu disampaikan pada
pasien setelah gigi tiruan dipasang yaitu: pada
malam hari pertama gigi tiruannya jangan dilepas
dahulu agar tidak terjadi pembengkakan; untuk
beberapa hari disarankan makan makanan yang
lunak dan membersihkan gigi tiruannya dengan
berkumur; hari kedua gigi tiruan sudah dapat
dilepas untuk dibersihkan dengan sikat halus dan
sabun dan kemudian segera dipakai kembali.
Selain itu pasien diberi obat antibiotik, anti
inflamasi dan analgetik untuk mencegah
terjadinya infeksi dan pembengkakan.3
Pasien diminta untuk kembali / kontrol
keesokan harinya, pada kunjungan ini operator
perlu memeriksa ada tidaknya penyimpangan
oklusi dan artikulasi. Kontrol selanjutnya satu
minggu kemudian untuk memeriksa kembali ada
tidaknya kesalahan oklusi , dan kontrol
berikutnya satu bulan kemudian untuk melihat
apakah sudah diperlukan perbaikan dengan
melakukan relining.
Contoh – Contoh Kasus Yang Memerlukan
Pembuatan Gigi Tiruan Sebagian Lepasan
Imidiat
Kasus I
Pasien pria 58 tahun , profesi sebagai
eksekutif ingin memperbaiki penampilan karena
gigi depan atas kiri terkena sundul cucunya
sehingga giginya goyang, pasien ingin
memperbaiki penampilan dan tidak ingin
mengalami periode tidak bergigi. Keadaan intra
oral: terdapat cantilever bridge dengan dukungan
pada gigi 21 dan 22 serta pontik diantara 11 dan
21 goyang derajat 3, mengalami ekstrusi,
gambaran rontgent foto terjadi resorpsi sampai
1/3 akar, gigi 12 dan 11 PFM, gigi gigi yang lain
tak ada kelainan.
Rencana perawatan:
Pembuatan gigi tiruan sebagian lepasan
imidiat dengan sayap pada gigi 21,22 dan gigi
diantara insisif sentral, pembuatan sayap ini
untuk memudahkan relining dikemudian hari,
mengingat gigi gigi sudah goyang derajat 3 dan
resorpsi yang akan terjadi lebih besar.
Tahap pekerjaan:
Pada kunjungan pertama dilakukan
anamnesis, pemeriksaan ekstraoral dan intraoral.
Selain itu dilakukan probing pada bagian labial –
lingual, mesial – distal dari regio yang nantinya
akan dilakukan ekstraksi yaitu regio 11,21,22.
Setelah itu dilakukan pencetakan rahang atas dan
rahang bawah serta seleksi warna dan bentuk
gigi.
Setelah didapatkan model kerja, dilakukan
peradiran pada regio 11,21,22 serta bagian labial
11, 21,22 untuk tempat sayap anterior dari gigi
tiruan lepasan imidiat sebelum dikirim ke
laboratorium gigi untuk dilakukan pembuatan
gigi tiruannya.
Pada kunjungan kedua setelah gigi tiruan
selesai. Pasien dilakukan ekstraksi pada BW
11,21,22 nya yang sudah longgar. Setelah
tindakan ekstraksi dilakukan, segera dilakukan
pemasangan gigi tiruan 11,21,22 dengan sayap
pada pasien. Pasien diinstruksikan untuk kontrol
setelah 24 jam. (Gambar.2.)
Gambar.2. Foto sebelum dan sesudah perawatan.
Estetik pasien tampak lebih baik
Kasus II
Pasien pria usia 20 tahun , bekerja sebagai
petugas kebersihan di sebuah rumah sakit, datang
ingin memperbaiki giginya yang patah.
Rencana perawatan:
Pembuatan gigi tiruan sebagian lepasan imidiat
dengan soket
Tahap pekerjaan:
Pada kunjungan pertama dilakukan
anamnesis, pemeriksaan ekstraoral dan intraoral.
Selain itu dilakukan probing pada regio
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 1-5
4
11,12,21,22. Setelah itu dilakukan pencetakan
rahang atas dan rahang bawah serta seleksi
warna dan bentuk gigi.
Setelah didapatkan model kerja, dilakukan
peradiran pada regio 11,12,21,22. Setelah itu
dikirim ke laboratorium gigi untuk dilakukan
pembuatan gigi tiruannya.
Pada kunjungan kedua setelah gigi tiruan
selesa. Pasien dilakukan ekstraksi gigi 11,12,22
nya yang fraktur. Setelah tindakan ekstraksi
dilakukan, segera dilakukan pemasangan gigi
tiruan lepasan imidiat dengan socket pada pasien.
Pasien diinstruksikan untuk kontrol setelah 24
jam. (Gambar.3)
Gambar.3. foto sebelum dan sesudah perawatan,
Tampak gigi tiruan imidiat dengan socket (tanpa
sayap)
Kasus III:
Pasien pria berusia 32 tahun, pedagang
kain, ingin dibuatkan gigi tiruan , gigi gigi 26,
36, 34, 32, 42, 46, sudah dicabut akibat kelainan
periodontal yang progresif, sedangkan gigi gigi
11, 21, 22, 31, 33, 34 dan 41 goyang derajat 3.
Pasien mengeluhkan estetik gigi anterior nya
yang tampak sudah modot dan goyang sehingga
menganggu aktifitas pekerjaannya sehari –hari.
Melalui pemeriksaan sendi rahang pasien
ditemukan adanya krepitasi pada sendi kiri dari
pasien. Tekanan darah dan gula darah masih
dalam batas normal.
Rencana perawatan:
Pembuatan gigi tiruan sebagian lepasan imidiat
dengan sayap penuh.
Tahap pekerjaan:
Kunjungan pertama:
Pencetakan Model Kerja RA dan RB dengan
bahan Alginate, pengukuran poket gigi regio 11,
21, 22, 31, 33, 34 dan 41.
Seleksi warna, bentuk dan ukuran gigi.
Surveying dan Penutupan Gerong Model Kerja.
Pemasangan model pada articulator.
Peradiran gigi 11, 21, 22, 33, 31 dan 41.
Menentukan Desain gigi tiruan.
Setelah itu dikirimkan ke laboratorium gigi untuk
dilakukan pembuatan gigi tiruan lepasannya
sesuai desain yang telah kita buat.
Kunjungan kedua:
Pencabutan gigi 11, 21, 22, 33, 31 dan 41.
Pemasangan gigi tiruan lepasan imidiat dengan
sayap penuh. (Gambar.4.)
Instruksi kepada pasien cara pemakaian gigi
tiruan dan datang kontrol 24 jam.
Gambar.4. foto sebelum dan sesudah perawatan,
Tampak estetik pasien jauh lebih baik
PEMBAHASAN
Pada Kasus I : gigi tiruan dibuat dengan
dengan sayap untuk memudahkan tindakan
relining, mengingat gigi gigi sudah mengalami
goyang derajat 3 dimana kemungkinan resorpsi
tulang alveolar lebih banyak.
Pada kasus II : Gigi tiruan imidiat dibuat
dengan soket agar seolah olah elemen gigi tiruan
berada pada posisi gigi aslinya , mengingat
daerah servikal dan akar gigi masih baik dimana
belum terjadi resorpsi dari alveolar penyangga
gigi yang dicabut.
Pada Kasus III : Sayap pada gigi tiruan
dari kasus ini berfungsi sebagai splint untuk
mengurangi rasa sakit, pembengkakan dan
perdarahan akibat tindakan ekstraksi regio gigi
yang cukup luas yaitu 11, 21, 22, 33, 31 dan 41.
Selain itu sayap gigi tiruan juga untuk menutupi
resorpsi tulang yang cukup besar karena adanya
periodontitis agresif generalized pada pasien.
KESIMPULAN
Pembuatan gigi tiruan imidiat anterior
merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi
keinginan pasien dengan segera guna
memperbaiki estetik dan fonetik yang biasanya
menyebabkan rasa rendah diri. Pada perawatan
pasien dengan pembuatan gigi tiruan imidiat
diperlukan perencanaan yang matang karena
tahap mencoba gigi tiruan malam tidak dapat
dilakukan sehingga pasien dan operator tidak
dapat menilai gigi tiruan tersebut terlebih dahulu
sebelum disalin ke akrilik.
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 1-5
5
DAFTAR PUSTAKA
1. Zarb GA, Hobkirk JA, Eckert SE, Jacob RF.
Prosthodontic Treatment for Edentulous
Patients Complete Denture and Implant
Supported Prostheses. Ed. Ke-13. St.Louis:
Elsevier; 2013: 152 -155.
2. Gunadi HA, dkk. Buku Ajar Ilmu Geligi
Tiruan Sebagian Lepasan Jilid II. Edisi 1.
Hipokrates, Jakarta: 1995: 367-378.
3. Bolender CL, Zarb GA. Buku Ajar
Prostodonti untuk Pasien Tidak Bergigi
Menurut Boucher. Ed. Ke-10. Penerjemah:
Mardjono ND. Jakarta: EGC Penerbit Buku;
1994: 456-480.
4. Winkler S. Essentials of Complete Dentures
Prosthodontics. Philadelphia: WB.Saunders;
1979: 517-538.
5. Jorgensen EB. Prosthodontic for the Elderly
(Diagnosis and Treatment). Ed ke-1. Chicago:
Quintessence; 1999: 153-167.
6. Ellinger CW, Rayson JH, Terry JH, Rahn
AD. Synopsis of Complete Denture.
Philadelphia: Lea & Febicer; 1975: 293-298.
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 6 – 9
6
Pengaruh Sikat dan Pasta Gigi Terhadap Kekasaran Permukaan Resin Komposit
Nanohibrida
(Laporan Penelitian)
Deviyanti Pratiwi1, Selvia Rizki Mulya2 1 Staf Pengajar Bagian Bahan Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti 2 Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti
ABSTRACT
Background: Nanohybrid composite resins have good mechanical durability and smooth surfaces.
The surface roughness of the composite resin restoration is often found in patients and may be caused
by the abrasive materials and mechanical activity of mechanical friction between tooth paste and
toothbrush with the surface of restoration. Aim: To determine the effect of brushes and toothpastes on
the surface roughness of nanohybrid composite resins. Methods: Comparison of surface roughness
using surface roughness tester before and after brushing on 8 samples of nanohybrid composite resins
with a diameter of 6 mm and a height of 3 mm. Brushing the sample is done using a brushing machine
simulation at a speed of 250 cycles per minute for 4 hours with a back and forth movement using a
toothbrush with medium brush bristles and adult toothpaste. Results: The paired t-test showed the
average value before brushing was 5.3788 ± 2.44104 µm and after brushing was 5.6700 ± 2.55310 µm
with p = 0.002 (p <0.05), meaning there was a difference in the surface roughness of the nanohybrid
composite resin significantly before and after brushing. Conclusion: Mechanical activities and
abrasive materials from the use of brushes and toothpaste that are routinely carried out have an effect
on the surface roughness of the nanohybrid composite resins.
Keyword: nanohybrid composite resins, toothbrush, toothpaste, abrasive, surface roughness
PENDAHULUAN
Resin komposit nanohibrida terdiri dari
partikel berukuran mikrometer dan nanometer
yang memiliki daya tahan mekanis yang baik
seperti komposit tipe macrofilled serta
menghasilkan permukaan yang halus seperti tipe
microfilled, sehingga resin tipe ini dapat
digunakan pada restorasi anterior maupun
posterior.1,2 Pada umumnya, resin komposit
nanohibrida memiliki komponen utama yang
sama seperti komposit lainnya yaitu matriks resin,
pengisi anorganik, pengikat dan bahan tambahan
seperti inisiator, akselerator, inhibitor, dan
pigmen. Hal yang membedakan hanyalah
ukurannya.3 Semakin kecil isi ukuran partikel,
semakin meningkatkan nilai estetik resin
tersebut.4
Perawatan kebersihan mulut sehari-hari
yaitu penggunaan sikat dan pasta gigi tidak dapat
dihindari. Abrasi utama dihasilkan dari gesekan
mekanis antara pasta gigi pada sikat gigi dengan
permukaan tumpatan. Hal ini berpengaruh
terhadap kekasaran permukaan tumpatan yang
dapat menyebabkan timbulnya masalah estetik
berupa perubahan warna pada tumpatan serta
memudahkan perlekatan koloni bakteri yang
dapat menyebabkan timbulnya karies sekunder.5,
Setiap substrat komponen tumpatan
memiliki ketahanan masing-masing terhadap
abrasi dari sikat dan pasta gigi. Cara penyikatan
gigi yang salah dapat menyebabkan pengikisan
pada permukaan tumpatan. Selain itu, pasta gigi
memiliki kandungan bahan abrasi yang tinggi
sehingga dapat merusak jaringan keras, jaringan
lunak dan restorasi, menyebabkan resesi gingiva,
abrasi servikal, dan dentin hipersensitivitas.6
Kalsium karbonat dan silika adalah bahan-bahan
yang pada umumnya menyebabkan abrasi. 6
METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah eksperimental
berupa uji laboratoris in vitro yang dilakukan di
laboratorium BKG dan Laboratorium metodologi
teknik industri Universitas Trisakti. Sebanyak 8
sampel resin komposit nanohibrida yang sesuai
kriteria yaitu berbentuk silindris, berukuran
diameter 6 mm dengan tinggi 3 mm, padat,
permukaan rata dan tidak berporus dilakukan uji
kekasaran permukaan yang diukur menggunakan
alat surface roughness tester.
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 6 – 9
7
Uji kekasaran permukaan dilakukan
sebanyak dua kali pada masing-masing sampel,
yaitu sebelum dan setelah dilakukan penyikatan
gigi dengan menggunakan pasta gigi. Sampel
diletakkan ke alat surface roughness tester dengan
posisi tidak boleh menggantung atau menekan.
Kekasaran permukaan dihitung sebagai
penyimpangan rata-rata arimetik terhadap lembah
atau dasar permukaan dan puncak permukaan,
dengan memakai salah satu parameter Ra dan µm
(mikrometer).
Gambar 1. Pengukuran kekasaran
Penyikatan sampel dilakukan
menggunakan mesin simulasi penyikatan gigi
pada kecepatan 250 siklus permenit selama 4 jam
dengan gerakan maju mundur dan kepala sikat
gigi berada di atas permukaan sampel. Penyikatan
selama 4 jam diasumsikan sebagai kebiasaan
menyikat gigi selama 2 menit dalam sehari selama
2 bulan. Penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan sikat gigi dengan bulu sikat
medium dan pasta gigi dewasa.
Gambar 2. Penyikatan sampel
HASIL
Setelah dilakukan penelitian dan
pengumpulan data dengan melakukan uji
kekerasan permukaan menggunakan alat surface
roughness tester (µm), dilakukan analisis statistik.
Hasil uji kekasaran permukaan pada sampel resin
komposit nanohibrida dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Perubahan kekasaran permukaan pada resin
komposit nanohibrida RESIN KOMPOSIT NANOHIBRIDA
Nomor
Sampel
Sebelum
A
Sesudah
B
Selisih
C
1 4,92 5,08 0,16
2 3,05 3,08 0,03
3 4,08 4,10 0,02
4 10,90 11,00 0,10
5 6,43 7,80 1,37
6 4,09 4,23 0,14
7 4,32 4,66 0,34
8 5,24 5,41 0,17
Uji t-berpasangan pada derajat kemaknaan
(p<0.05) digunakan untuk melihat ada tidaknya
perbedaan hasil yang signifikan.
Tabel 2. Analisis statistik kekasaran permukaan resin
komposit nanohibrida (µm) sebelum dan sesudah
penyikatan dengan pasta gigi.
Variabel N Mean SD P -Value
Sebelum
Penyikatan
Komposit
8 5.3788 2.44104
0,002 Sesudah
Penyikatan
Komposit
8 5.6700 2.55310
Hasil perhitungan uji t berpasangan pada
komposit didapatkan nilai rata-rata sebelum
penyikatan gigi selama 4 jam adalah 5.3788 ±
2.44104 µm dan sesudah penyikatan adalah
5.6700± 2.55310 µm dengan nilai p = 0.002
(p<0.05), artinya terdapat perbedaan terhadap
kekasaran permukaan komposit sebelum dan
sesudah penyikatan selama 4 jam secara
signifikan.
PEMBAHASAN
Abrasi utama dihasilkan dari pasta gigi dan
sikat gigi. Permukaan kasar akan mempengaruhi
adhesi bakteri dengan meningkatkan retensi plak.
Hasil penelitian sebelumnya mengenai sikat gigi
pada orang dewasa telah menunjukkan tingkat
abrasi yang berbeda akibat dari tinggi atau lebih
rendah filamen atau kontak pasta gigi daerah
dengan permukaan substrat.7,8 Perbedaan
kharateristik bahan abrasif yang terdapat pada
setiap pasta gigi juga dapat menimbulkan tingkat
kekasaran permukaan yang berbeda.6,9 Abrasi
yang timbul akibat aktivitas menyikat gigi
merupakan suatu fenomena yang sering
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 6 – 9
8
ditemukan pada permukaan bukal gigi maupun
restorasi.10
Hasil analisis statistika uji t–berpasangan
resin komposit nanohibrida menunjukkan
terjadinya peningkatan kekasaran permukaan
dengan nilai p=0.002 (p<0.05), maka hipotesa
penelitian (H0) ditolak, sehingga dapat diartikan
adanya perbedaan kekasaran permukaan antara
resin komposit nanohibrida sebelum dan sesudah
penyikatan secara signifikan atau bermakna. Hasil
penelitian ini didukung oleh penelitian Carolina
dkk yang menyatakan bahwa resin komposit yang
disikat dengan pasta gigi yang mengandung bahan
abrasif menyebabkan kerusakan pada substrast
yang mampu mengubah kekasaran permukaan
pada resin komposit.11 Penelitian oleh Monteiro
dkk juga menyebutkan bahwa sikat gigi
mempengaruhi peningkatan kekasaran
permukaan resin komposit, semakin lama waktu
menyikat maka semakin meningkat kekasaran
permukaan komposit.6
Resin komposit nanohibrida terdiri dari
kombinasi ukuran partikel filler sehingga ikatan
antara filler dan matrix menjadi lebih kuat. Resin
komposit nanohibrida juga memiliki banyak
kandungan bahan filler, sehingga memiliki
ketahanan yang kuat terhadap suasana asam.12,13,14
Akan tetapi, sifat suatu material kedokteran gigi
yang dapat menyerap air dan larut dalam air juga
dapat mempengaruhi kelenturan, kekuatan tekan,
dan kekasaran permukaan bahan restorasi.
Penelitian sebelumnya juga membuktikan bahwa
kekasaran permukaan terjadi pada semua restorasi
komposit, tidak ditemukan perbedaan kekasaran
yang timbul akibat aktivitas menyikat gigi pada
komposit nanohibrid dan nanokomposit.6
Kekasaran permukaan pada bahan restorasi
dapat meningkatkan kemungkinan kolonisasi
bakteri dan maturasi plak sehingga memperbesar
kemungkinan terjadinya karies sekunder dan
inflamasi pada jaringan periodontal.15 Terdapat
berbagai cara yang dipakai untuk mengatasi
proses penyusutan dan mencegah peningkatan
kekasaran permukaan pada tumpatan, seperti:
menambah bonding agent, menambah lapisan
daya tahan elastis, meningkatkan intensitas light
curing, memakai teknik peletakan bahan resin
komposit lapis demi lapis, menggunakan
monomer low-shrinking dan memasukkan bahan
fluoride pada monomer resin untuk mencegah
terjadinya marginal gaps pada kavitas.16
Struktur kompleks dari suatu permukaan
bahan tidak hanya cukup diukur menggunakan
alat surface roughness tester, banyak penelitian
yang menyarankan untuk dilakukan kombinasi
pengujian dengan menggunakan analisis SEM
dengan tujuan melakukan evaluasi ulang.12
KESIMPULAN
Hasil pengujian ini menunjukkan pengaruh
aktifitas mekanis dan bahan abrasive pada
penggunaan sikat dan pasta gigi terhadap
kekasaran permukaan tumpatan. Kekasaran
permukaan tumpatan sesudah penyikatan gigi
lebih besar dibandingkan sebelum penyikatan
gigi menggunakan sikat gigi dewasa dengan
bulu sikat medium dan pasta gigi pada
permukaan tumpatan resin komposit
nanohibrida.
SARAN
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap
kelompok sampel yang lebih besar atau
frekuensi penyikatan yang lebih lama agar
didapat tingkat validitas yang lebih tinggi
sehingga perubahan sifat kekasaran permukaan
yang disikat terlihat lebih jelas.
DAFTAR PUSTAKA
1. Sakaguchi R, Powers J. Craig’s restoration
dental materials. 13th ed. Saint Louis:
Elsevier; 2012. 161-75.
2. Jain A, Deepthi D, Tavane PN, Singh A,
Gupta A, Sonkusre S. Evaluation of
microleakage of recent nano-hybrid
composites in class v restorations: An in vitro
study. Int J Adv Heal Sci. 2015;2(1): 8-12.
3. Moares RR, Concalves JS, Lancerlloti AC.
Nanohybrid Resin Composites: Nanofiller
Loaded Materials or Traditional
Mycrohybrid Resins. Operative Dentistry.
2009; 34(5): 551-557.
4. Maghfiroh H, Nugroho R, Probosari N. The
Effect of Carbonated Beverage to The
Discoloration of Polished and Unpolished
Nanohybrid Composite Resin. J
Dentomaxillofac Sci. 2016; 1(1) : 19-27.
5. Tantanuch S, Kukiattrakoon B,
Peerasukprasert T, Chanmanee N,
Chaisomboonphun P, Rodklai A. Surface
roughness and erosion of nanohybrid and
nanofilled resin composites after immersion
in red and white wine. J Conserv Dent. 2016;
19 (1): 51-5
6. Monteiro B, Spohr AM. Surface Roughness
of Composite Resins after Simulated
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 6 – 9
9
Toothbrushing with Different Dentifrices. J
Int Oral Health 2015; 7(7): 1–5.
7. Paula AB, Correr GM, Sinhoreti MAC,
Puppin-rontani RM. Child Toothbrush
Abrasion Effect on. J Dent child. 2008.
8. Hussein TA, Zaripah W, Bakar W, Ghani
ZA, Mohamad D. The assessment of surface
roughness and microleakage of eroded tooth-
colored dental restorative materials. J
Conserv Dent. 2014;17(6):531–6.
9. Liljeborg A, Tellefesen G, Johannsen G. The
use of a profilometer for both quantitative
and qualitative measurements of toothpaste
abrasivity. Int J Dent Hyg 2010; 8 (3): 237-
43.
10. Chimello, DT, Palma-Dibb RG, Corona SA,
Lara E. Assessing wear and surface
roughness of different composite resins after
tooth brushing. Mater Res 2001; 4: 285-9.
11. Carolina A, Rocha DC, Santiago C, Lima A
De, Moreira C, Antonio M, et al. Evaluation
of Surface Roughness of a Nanofill Resin
Composite After Simulated Brushing and
Immersion in Mouthrinses, Alcohol and
Water. Material Research.2010;13(1):77–80.
12. Ergucu Z, Turkun LS. Surface roughness of
novel resin composites polished with one
step systems. Oper Dent. 2007; 32(2): 185-
92
13. Han L, Okamoto A, Fukushima M, Okiji T.
Evaluation of flowable resin composite
surface eroded by acidic and alcoholic
drinks. Dent Mater J. 2008; 27(3):455-65.
14. Alifen GK, Soetojo A, Saraswati W.
Differences in surface roughness of
nanohybrid composites immersed in varying
concentrations of citric acid. Dent Journal.
2017 June; 50(2): 102-5.
15. Gigi JK, Permatasari AP, Yanuar M, Nahzi I.
Kekasaran Permukaan Resin Modified Glass
Ionomer Cement Setelah Perendaman Dalam
Air Sungai (Penelitian Menggunakan Air
Sungai Desa Anjir Pasar, Barito Kuala ,
Kalimantan Selatan ). Dentino Jur Ked
Gigi.2016;1(2):164-168.
16. Susanto AA. Pengaruh ketebalan bahan dan
lamanya waktu penyinaran terhadap
kekerasan permukaan resin komposit sinar.
Dent J. 2007; 38(1) :32–35.
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 10 – 16
10
Pengaruh Bahan Bleaching Karbamid Peroksida 20% Dan 35% Terhadap Kekerasan
Resin Komposit Tipe Nano Hibrid
(Laporan Penelitian)
Dewi Liliany Margaretta1, Reinaldo Sugianto2 1 Staf Pengajar Bagian Bahan Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti 2 Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti
ABSTRACT
Background: Studies have shown that the majority of adults are not satisfied with the color of their
teeth. This dissatisfaction leads to the increasing of bleaching demands. However, free radicals in
bleaching agents may have an effect to the composite resin restoration hardness. Aim: To compare the
effect of carbamide peroxide 20% and 35% on nanohybrid resin composite hardness. Methods:
Samples were nanohybrid resin composite with 4 mm thickness and 10 mm diameter. Total number is
10 samples with 5 testing points on each sample, and divided into 3 groups: control group, application
of 20% carbamide peroxide for 7 and 14 days, and application of 35% carbamide peroxide for 7 and
14 days. Each group was tested using Vickers Hardness Test. Results: The results indicate there was
no significant effect of 20% carbamide peroxide on resin composite hardness for 7 days with p = 0.980
(p > 0.05) and 35% for 7 days with p = 0.994 (p > 0.05), but the use of carbamide peroxide 20% and
35% on a nanohybrid resin composite for 14 days led to a significant increase in hardness with p =
0.000 (p<0.05). Conclusion: The use of carbamide peroxide 20% and 35% for 7 and 14 days did not
cause hardness decrease on nanohybrid resin composite.
Keyword: bleaching, carbamide peroxide, resin composite, hardness
PENDAHULUAN
Dewasa ini masyarakat mulai menyadari
mempunyai gigi yang indah adalah salah satu
aspek penting dalam meningkatkan kepercayaan
diri sehingga banyak orang rela mengeluarkan
biaya yang relatif tidak sedikit untuk memperbaiki
penampilan gigi mereka. Dari 235 pasien yang
terdiri dari 70 pria (29,8%) dan 165 wanita
(70,2%), dengan partisipan berumur 18 – 62
tahun, sebanyak 124 pasien (52,8%) menyatakan
bahwa mereka tidak puas dengan penampilan gigi
mereka, dan sebanyak 132 pasien (56,2%)
menyatakan tidak puas dengan warna gigi
mereka.1 Ketidakpuasan inilah yang
menyebabkan permintaan terhadap pemutihan
gigi (bleaching) semakin meningkat. Fungsi dari
bleaching adalah untuk menghilangkan
pewarnaan akibat stain dan memutihkan kembali
gigi yang telah berubah warna sehingga
mengembalikan estetik gigi.2
Perubahan warna gigi dapat berlangsung
secara fisiologik dan patologik. Perubahan warna
gigi secara fisiologik terjadi seiring dengan
pertambahan umur, dikarenakan dentin menjadi
lebih tebal dengan adanya deposisi dentin
sekunder, juga email gigi menjadi lebih tipis
akibat fungsi pengunyahan. Perubahan warna gigi
secara patologik bisa bersifat intrinsik dan
ekstrinsik. Perubahan warna gigi secara intrinsik
disebabkan oleh faktor dari jaringan gigi atau
jaringan pulpa sedangkan perubahan warna gigi
secara ekstrinsik dapat terjadi karena adanya
deposit yang melekat pada permukaan gigi seperti
dari makanan dan minuman.2,3
Metode pemutihan gigi yang umum
digunakan ada 2 yaitu in-office bleaching dan
home bleaching. In-office bleaching merupakan
metode yang dilakukan di klinik dokter gigi dan
dilakukan oleh dokter gigi dengan bahan hidrogen
peroksida konsentrasi 30-55%, sedangkan home
bleaching dilakukan di rumah pasien yang
pemakaiannya di bawah pengawasan dokter gigi.
Kekurangan dari in-office bleaching ini adalah
harganya yang relatif mahal sehingga banyak
orang lebih menaruh pilihannya terhadap home
bleaching, meskipun hasil dari in-office bleaching
lebih cepat.4
Bahan untuk home bleaching biasanya
menggunakan karbamid peroksida kadar 10-22%.
Rumus molekul untuk karbamid peroksida adalah
CO(NH2)2H2O2. Karbamid peroksida memiliki
nama kimia urea hidrogen peroksida dengan berat
molekul 94,07.5 Karbamid peroksida 10% akan
terurai menjadi urea, amonia, karbondioksida dan
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 10 – 16
11
sekitar 3,5% hidrogen peroksida.6 Hidrogen
peroksida berperan dalam mekanisme pemutihan
sedangkan urea menstabilkan bahan pemutih
sehingga memiliki efek obat yang panjang dan
memperlambat pelepasan hidrogen peroksida
yang menghasilkan karbamid peroksida memiliki
bentuk lebih stabil jika dibandingkan dengan
hidrogen peroksida.7
Sebagai bahan restorasi, resin komposit
sudah umum dan populer digunakan, mengingat
komposit mempunyai segi estetik yang baik dan
dapat menahan daya kunyah yang cukup tinggi.
Resin komposit adalah tambalan yang sewarna
gigi dan merupakan material kompleks serta
mengandung komponen resin organik yang
membentuk matriks, inorganic filler, coupling
agent untuk menyatukan resin dengan filler,
initiator untuk mengaktifkan mekanisme setting
komposit, stabilisers dan pigmen. Berdasarkan
ukuran partikel filler, resin komposit dapat dibagi
menjadi 4 yaitu makrofil, mikrofil, hibrid dan
hibrid partikel kecil (Small-particle hibrid) resin
komposit. Nano hibrid resin komposit merupakan
salah satu jenis hibrid resin komposit yang
mengandung partikel filler berukuran nano
(0,005-0,01μ) pada matriks resinnya.
Populernya penggunaan nano hibrid resin
komposit disebabkan oleh kemampuan
penanganan dan pemolesan dari mikrofil
komposit, juga kekuatan dan ketahanan
pemakaian dari makro hibrid komposit sehingga
dapat digunakan sebagai bahan restorasi baik pada
gigi anterior maupun gigi posterior, oleh karena
itu nano hibrid komposit dapat disebut sebagai
bahan tambal yang universal.8
Seiring banyaknya praktek bleaching
dilakukan, banyak masyarakat tidak sadar bahwa
penggunaan bahan pemutih gigi home bleaching
dengan kadar yang berbeda mempunyai efek
beragam terhadap kekerasan tambalan resin
komposit tipe nano hibrid. Studi yang dilakukan
Baskar SH., dkk (2016) menunjukkan kekerasan
resin komposit mikrohibrid tidak berubah setelah
diaplikasi bahan bleaching karbamid peroksida
10%, 20% dan 35%.9 Sedangkan Bahamari M.,
dkk (2016) menyatakan bahwa penggunaan
karbamid peroksida 15% pada resin komposit
silorane dapat menurunkan kekerasan.10 Dari
uraian di atas dapat dilihat bahwa belum ada
penggunaan karbamid peroksida 20% dan 35%
terhadap resin komposit nano hibrid sehingga
tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
perbandingan penggunaan karbamid peroksida
20% dan 35% terhadap kekerasan resin komposit
tipe nano hibrid.
METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian
eksperimental laboratorik untuk mengetahui
perbandingan pengaruh penggunaan bahan
bleaching karbamid peroksida 20% dan 35%
terhadap kekerasan resin komposit tipe nano
hibrid. Penelitian ini dilakukan di Micore Fakultas
Kedokteran Gigi Universitas Trisakti dan
Laboratorium Metalurgi Universitas
Indonesia.pada bulan Januari 2017. Sampel
penelitian adalah resin komposit tipe nano hibrid
merek 3M Espe FiltekTM Z250 XT berbentuk
silinder dengan diameter 10 mm dan tinggi 4 mm.
Terdapat 3 kelompok dimana total sampel yang
digunakan adalah 10 buah. Kelompok 1
merupakan kelompok kontrol. Kelompok 2
menggunakan karbamid peroksida 20% dengan
waktu perendaman 7 dan 14 hari. Kelompok 3
menggunakan karbamid peroksida 35% dengan
waktu perendaman 7 dan 14 hari.
Pembuatan Sampel
Pemakaian masker dan sarung tangan.
Resin komposit tipe nano hibrid dimasukkan ke
dalam cetakan sampel yang telah dilapisi vaseline
dan ditaruh di atas gelas kaca menggunakan
instrumen plastis. Cetakan sampel yang telah
terisi penuh oleh komposit dilapisi seluloid strip
yang ditimpa anak timbangan 100 gram sampai
permukaan sampel rata. Komposit kemudian di
light cure dari atas dan bawah masing-masing
selama 20 detik dengan jarak penyinaran ±1 mm,
lalu sampel dikeluarkan dari cetakan dan
dilanjutkan dengan pemolesan menggunakan bur
poles.
Tahap pembuatan sampel diulang hingga
didapatkan 10 sampel. Dua dari sepuluh sampel
ditandai sebanyak 5 titik di tengah pada salah satu
sisi sampel menggunakan spidol hitam. Empat
sampel lainnya diberikan tanda sebanyak 5 titik
pada salah satu sisi sampel di tengah
menggunakan spidol biru. Perlakuan yang sama
diberikan pada empat sampel terakhir
menggunakan spidol merah. Sampel yang telah
ditandai spidol hitam adalah kelompok kontrol,
yang ditandai spidol biru adalah kelompok 2 yaitu
resin komposit tipe nano hibrid yang
diaplikasikan karbamid peroksida 20%, dan yang
ditandai spidol biru adalah kelompok 3 yaitu resin
komposit tipe nano hibrid yang diaplikasikan
karbamid peroksida 35%.
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 10 – 16
12
Pengaplikasian Bahan Bleaching Tiap kelompok direndam dalam wadah
plastik berbeda yang berisikan akuades.
Ketigakelompok tersebut diinkubasi di dalam
inkubator dengan suhu 37ºC selama 24 jam.
Sampel kelompok 1 tidak diberikan perlakuan
apapun. Sampel kelompok 2 dan 3 dikeluarkan
dari wadah plastik menggunakan pinset. Sampel
kelompok 2 diaplikasikan bahan bleaching
karbamid peroksida 20% dan sampel kelompok 3
dengan karbamid peroksida 35% menggunakan
instrumen plastis pada sisi yang telah ditandai
secara merata, lalu dimasukkan ke dalam wadah
plastik kosong yang berbeda.
Kelompok 2 ditaruh di dalam inkubator
selama 2 jam dan kelompok 3 ditaruh selama 30
menit. Sampel dikeluarkan dari wadahnya
masing-masing menggunakan pinset, lalu dicuci
menggunakan akuades sampai bersih dari bahan
bleaching. Setelah bersih, sampel kembali
dimasukkan ke dalam wadah yang berisikan
akuades dan ditaruh di dalam inkubator selama 24
jam ke depan. Hal ini dilakukan secara berulang
dengan total 14 hari.
Pengujian Kekerasan
Kekerasan sampel diuji pada titik yang
telah ditandai spidol dengan alat uji kekerasan
Vickers Hardness Tester dengan load 100 gf
selama 10 detik. Pengujian pada kelompok 1
dilakukan pada sisi yang diberi tanda titik hitam
setelah perendaman akuades selama 24 jam.
Kelompok 2 diuji pada sisi yang diberi tanda titik
biru dan kelompok 3 akan diuji pada sisi yang
telah diberi tanda titik merah pada hari ke 7 dan
14.
HASIL PENELITIAN
Setelah dilakukan penelitian dan
pengumpulan data, dilakukan uji statistik
menggunakan metode analisis, yaitu uji
normalitas dengan metode Shapiro-wilk. Data
hasil penelitian dinyatakan normal dan homogen
jika pada uji normalitas dan homogen nilai p >
0.05, setelah itu dilanjutkan dengan One Way
ANOVA. Jika data menunjukkan ada perbedaan
bermakna maka data dianalisis menggunakan Uji
Post Hoc Tukey.
Besar sampel yang digunakan pada
penelitian ini sebanyak 10 buah tiap kelompok
perlakuan dan setiap sampel mengalami 5 titik
pengukuran. Uji kekerasan dilakukan di
Laboratorium Metalurgi Universitas Indonesia
dengan hasil dalam satuan VHN (Vickers
Hardness Number). Data-data hasil pengujian
adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Nilai Kekerasan Resin Komposit
No.
Sampel
Kekerasan (VHN)
Kontrol Karbamid
Peroksida 20%
Karbamid
Peroksida 35%
7 hari 14 hari 7 hari 14 hari
1 103 110 287 112 296
2 103 105 295 99 340
3 110 114 261 105 337
4 105 109 287 112 288
5 100 102 337 105 315
6 103 109 295 112 304
7 103 106 287 99 304
8 108 109 261 107 318
9 105 113 340 109 292
10 103 103 285 110 300
Rerata
± SD
104,30
± 2,869
108 ±
3,972
293,50
±
26,605
107 ±
4,989
309,40
±
17,921
Dari hasil di atas dapat dilihat bahwa
pemakaian karbamid peroksida 20% dan 35%
selama 7 hari tidak menyebabkan kenaikan
dan penurunan yang signifikan pada
kekerasan resin komposit nano hibrid.
Sedangkan untuk pemakaian selama 14 hari,
hanya ada kenaikan dan tidak ada penurunan.
Kekerasan tertinggi merupakan setelah
pengaplikasian karbamid peroksida 35%
selama 14 hari (309,40 ± 17,921). (Tabel 1). Tabel 2. Uji One Way ANOVA
Mean
Square F Sig.
Between
Groups 114428,830 530,801 ,000
Within
Groups 215,578
Total
Pada uji One Way Anova didapatkan hasil p
= 0,000 (p< 0,005). Hal ini membuktikan bahwa
terdapat perbedaan bermakna sehingga dapat
dilanjutkan dengan uji Post Hoc Tukey.
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 10 – 16
13
Tabel 3. Uji Post Hoc Tukey
Kontrol
KP
20% 7
hari
KP
20%
14 hari
KP
35% 7
hari
KP 35%
14 hari
Kontrol ,980 ,000* ,994 ,000*
KP
20% 7
hari
,980 ,000* 1,000 ,000*
KP
20% 14
hari
,000* ,000* ,000* ,128
KP
35% 7
hari
,994 1,000 ,000* ,000*
KP
35% 14
hari
,000* ,000* ,128 ,000*
Tanda * menandakan p > 0,05
Berdasarkan uji statistik di atas, jika
dibandingkan dengan kelompok kontrol kenaikan
kekerasan resin komposit setelah pengaplikasian
karbamid peroksida 20% selama 7 hari dengan p
= 0,980 (p>0,005) tidak signifikan. Hal yang
sama dapat dilihat pada kelompok yang diaplikasi
karbamid peroksida 35% selama 7 hari dengan p
= 0,994 (p>0,005). Namun pemakaian karbamid
peroksida kadar 20% dan 35% selama 14 hari
menyebabkan kenaikan kekerasan yang
signifikan dengan p masing-masing sama dengan
0,000 (p< 0,005).
PEMBAHASAN
Mekanisme kerja bahan bleaching
peroksida adalah hidrogen peroksida masuk
melalui perantara email menuju ke tubuli dentin
dan melepaskan oksigen yang akan merusak
ikatan dalam rantai protein yang bergabung
dengan stain. Dengan penambahan oksigen,
molekul organik gigi yang lebih kecil akan
terbentuk dengan warna yang lebih cerah.
Karbamid peroksida 10% akan terurai
menjadi urea, amonia, karbondioksida dan sekitar
3,5% hidrogen peroksida. Kandungan hidrogen
peroksida pada karbamid peroksida akan terurai
sebagai radikal bebas yaitu perihidroksil sebagai
oksidator kuat dan oksigenase sebagai oksidator
lemah. Hal ini menimbulkan anggapan bahwa
radikal bebas yang dihasilkan karbamid peroksida
kadar 20% dan 35% mempunyai efek terhadap
kekerasan terhadap tambalan resin komposit nano
hibrid pasien. Kekerasan resin komposit diukur
menggunakan Vickers Hardness Test dengan
satuan VHN (Vickers Hardness Number).
Berdasarkan penelitian yang telah
dilakukan, dapat terlihat bahwa pemakaian
Opalescence karbamid peroksida 20% dan 35%
pada nano hibrid komposit 3M Filtek Z250 XT
selama 7 hari menyebabkan kenaikan dan
penurunan kekerasan walaupun tidak signifikan
jika dibandingkan dengan grup kontrol. Hasil
penelitian ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Baskar SH., dkk (2016) yang
menyatakan bahwa kekerasan resin komposit
Z250 tidak terpengaruh dengan penggunaan
karbamid peroksida 10%, 20% dan 35% selama 7
hari jika digunakan sesuai dengan instruksi
penggunaan.9
Pemakaian karbamid peroksida 20% dan
35% selama 14 hari pada komposit 3M Filtek
Z250 XT menyebabkan kenaikan kekerasan yang
signifikan jika dibandingkan dengan kelompok
kontrol. Hasil penelitian ini didukung oleh
penelitian yang dilakukan Alaghehmand H, dkk
(2013) yang meneliti bahwa penggunaan
Opalescence karbamid peroksida 20% selama 4
minggu pada Filtek P60 memberikan kenaikan
kekerasan yang signifikan.44 Hasil penelitian
serupa juga dikemukakan oleh Ab-Ghani Z., dkk
(2013) yang meneliti dan menemukan bahwa
terdapat kenaikan kekerasan yang signifikan pada
nano komposit (KeLFiL) setelah pemakaian
karbamid peroksida 10% selama 14 hari. 45
Akan tetapi hasil penelitian ini
bertentangan dengan hasil penelitian yang
dilakukan oleh Sharafeddin F., dkk (2010)
yang menyatakan bahwa pemakaian
karbamid peroksida 35% selama 3 minggu
tidak memberikan efek yang berarti terhadap
kekerasan resin komposit mikrofil
(Heliomolar) dan hibrid (Spectrum TPH).46
Hasil bertentangan lain dikemukakan oleh
Bahari M., dkk (2016) yang meneliti dan
menyimpulkan bahwa pemakaian karbamid
peroksida 15% selama 2 minggu dapat
menurunkan kekerasan resin komposit
silorane secara signifikan.10 Terjadinya penurunan kekerasan pada
penelitian ini bisa disebabkan oleh human error
dimana pemolesantidak adekuat sehinggatidak
menghilangkan surface layer yang brittle.
Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi
penurunan kekerasan resin komposit adalah
kerentanan resin komposit terhadap pelunakan
kimia jika bahan kimia tersebut mempunyai
parameter kelarutan dari 1.82x104 sampai
2.97x104 (J/m3)1/2 serta kandungan Bis-GMA
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 10 – 16
14
monomer yang banyak pada resin komposit.47
Penurunan kekerasan resin komposit juga dapat
disebabkan karena oksidasi dan degradasi ikatan
matriks.48 Semakin banyak kandungan inorganik
filler maka semakin bagus pula sifat fisik suatu
resin komposit.34 Padatnya kandungan filler pada
Z250 XT yaitu 68% by volume mungkin
memberikan resistensi terhadap oksidasi dan
degradasi ikatan matriks. Minimnya penurunan
kekerasan setelah aplikasi bahan bleaching
merupakan bukti bahwa Filtek Z250 XT
mempunyai kandungan Bis-GMA yang rendah
dan kandungan filleryang tinggi untuk dapat
terjadi pelunakan kimia (penurunan kekerasan).
Sedangkan untuk kenaikan kekerasan resin
komposit dapat disebabkan karena reaksi
polimerisasi. Reaksi polimerisasi komposit
berbanding lurus dengan kenaikan kekerasan
komposit. Setelah proses curing komposit, reaksi
polimerisasi (post polimerisasi) akan tetap
berlangsung sampai jangka waktu tertentu.49
Kemungkinan efek yang dihasilkan oleh bahan
bleaching karbamid peroksida 20% dan 35% tidak
cukup besar untuk mempengaruhi proses
polimerisasi resin komposit tipe nano hibrid
sehingga reaksi post polimerisasi tetap
berlangsung.
Kemungkinan lainnya adalah bahan aktif
pada karbamid peroksida dapat menghilangkan
lapisan terluar pada resin komposit nano hibrid
sehingga menghasilkan permukaan yang lebih
padat akan kandungan filler dan lebih keras.
Adanya efek kandungan fluoride yang terdapat
pada karbamid peroksida 20% dan 35%, juga
dapat memberikan efek remineralisasi yang
berujung pada penambahan kekerasan pada resin
komposit. Dengan adanya kenaikan kekerasan
maka dapat dikatakan karbamid peroksida 20%
dan 35% merupakan bahan bleaching yang aman
digunakan dan mempunyai efek yang baik
terhadap kekerasan resin komposit Filtek Z250
XT tipe nano hibrid. Kenaikan kekerasan resin
komposit dapat memberikan berbagai keuntungan
antara lain dapat menahan daya tekanan kunyah
yang lebih besar, perubahan bentuk dan tambalan
aus lebih bisa diminimalisir dan rentang
pemakaian yang lebih panjang.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, jika dibandingkan
dengan grup kontrol maka dapat disimpulkan
bahwa pemakaian karbamid peroksida 20% dan
35% baik selama 7 maupun 14 hari
tidakmenyebabkan penurunan terhadap kekerasan
resin komposit tipe nano hibrid.
DAFTAR PUSTAKA
1. Oo MMT, Saddki N, and Hassan N. “Factors
Influencing Patient Satisfaction with Dental
Appearance and Treatments They Desire to
Improve Aesthetics. BMC Oral Health.
2011; 11: 6.
2. Rasinta T. Perawatan pulpa gigi. Seri 1.
Jakarta: Widya Medika; 1994; 198.
3. Sundoro EH. Serba-serbi ilmu konservasi
gigi. Jakarta: UI-Press; 2005; 17.
4. Rismanto, D.Y, Damayanti, I. M, Dharmo,
R. H., “Dental Whitening”,Dental Limas
Mediatama, Jakarta, 2005; 1-44.
5. Walsh LJ. Safety Issue Relating to the use of
Hydrogen Peroxide in Dentistry. Australian
Dental Journal. 2000;45(4):257-69.
6. Walton RE dan Torabinejad M. Prinsip Dan
Praktik Ilmu Endodonsia. 3rd ed. Jakarta:
EGC, 2008: 459.
7. Goldstein RE, Garber DA. Chemistry of
Bleaching. Complete Dental Bleaching.
Chicago: Quintessence, Publ., 1995; 2-20.
8. Puckett AD, Fitchie JG, Kirk PC, et al. Direct
Composite Restorative Materials. Dent Clin
N Am. 2007; 51: 659-75.
9. Baskar SH, Jayakumar M, Kumar S. Effect
of varying concentrations of home bleaching
agents on hardness of a resin composite: An
in vitro study. J Indian Acad Dent Spec Res.
2016; 3: 1-5
10. Bahari M, Savadi OS, Mohammadi N,
Ebrahami CME, Godrati M, Savadi OA.
Effect of different bleaching strategies on
microhardness of a silorane-
based composite resin. J Dent Res Dent Clin
Dent Prospects. 2016 Fall;10(4): 213-19.
11. Jakfar S. Pengaruh Agen Aktif Bleaching
Terhadap Jaringan Keras dan Lunak Mulut
Serta Bahan Restorasi Kedokteran Gigi. Cak
Dent J 2009 ; 2(1): 62-9.
12. Matis BA. The question-at-home or in-office
bleaching: Evidence based concepts to
empower dental professionals. Available at:
[email protected]. Accesed August 27,
2004.
13. Boksman, L., “Current Status of Tooth
Whitening”, Literature Review, September,
2006; 76-79.
14. Wagner, B. J., “Whiter Teeth-Brighter
Smiler”, Special Supplemental issue-Access,
September-Oktober, 1999; 1-12.
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 10 – 16
15
15. Suprastiwi, E., “Penggunaan Karbamid
Peroksida sebagai Bahan Pemutih Gigi”, Ind.
J. Dentistry, 2005; 12(3): 139-45.
16. Goldstein RE, Garber DA. Complete Dental
Bleaching. Chicago: Quintessence
Publishing Co.Inc, 1995 : 26-33.
17. Nakamura, T., Saito, O., Ko, T., Maruyama,
T., “The Effect of Polishing and Bleaching
on The Colour oh Discoloured Teeth in
Vivo”, J. Oral Rehab., 2001; 28, 1080-4.
18. Hatrick CD, Eakle WS, Bird WF. Dental
Materials: Clinical Applications for Dental
Assistants and Dental Hygienists. 2nd Ed.
USA : Saunders Elsevier. 2011: 50-86.
19. Bernie KM., “Maintaining Tooth-Whitening
Results”, J. Pract. Hygiene, 2003; 34-36.
20. Vanable ED dan LoPresti, L. R, “Using
Dental Material”, Pearson Prentice Hall,
New Jersey, 2004; 80-5.
21. Ingle, J. I., Bakland, L. K., “Endodontics”,
5th ed, BC Decker Inc, Hamilton London,
2002; 849-50.
22. Halim HS. Perawatan Diskolorisasi Gigi
Dengan Teknik Bleaching. Jakarta:
Universitas Trisakti, 2006; 1-75.
23. Grossman LI, Oliet S, Rio CED. Ilmu
Endodontik Dalam Praktek. Edisi ke 11. Alih
Bahasa. Rafiah A. Jakarta : EGC, 1995; 295-
7.
24. Haywood VB., “Nightguard Vital Bleaching
Indications and Limitation”s, US Dentistry,
Section Heading Sub Heading, 2006; 2-8.
25. Gunawan HA., “Pengaruh Pemutih Gigi
Karbamid Peroksida terhadap Mukosa
Rongga Mulut secara Mikroskopik
(Penelitian pada Tikus Wistar Strain LMR)”,
J, Ked. Gigi UI, 10 (Edisi Khusus), 2003;
652-6.
26. Hewlett ER., “Etiology and Management of
Whitening-induced Tooth Hypersensitivity”,
J. CDA, 35 (7), 2007; 499-506.
27. Leevailoj C. The Art of Anterior Tooth-
Colored Restoration with Resin Composites.
Thailand: Chulalongkorn University, 2004:
10-4.
28. Meizarini A, Rianti D. Bahan Pemutih Gigi
Dengan Sertifikat ADA/ISO. Maj. Ked Gigi
2005; 38 (2) : 73-6.
29. Mitchell C. Dental Materials in Operative
Dentistry.Quintessence Publishing Co.
Ltd., 35(1), 2008: 1-21.
30. Anusavice KJ, Shen C, and Rawls HR.
Philip’s Science of Dental Materials. 12th ed.
Singapore: Elsevier, 2013; 279-91.
31. O’Brien, William J.. Dental Materials and
Their Selection. 3rd ed. Canada:
Quintessence, Publ., 2002; 113-28.
32. Irawan B. “Material Restorasi Direk
Kedokteran Gigi Saat Ini.” Journal Dentistry
Indonesia, 2004; 24–8.
33. Mount GJ and Hume WR. Preservation and
Restoration of Tooth Structure. Barcelona:
Mosby, 1998; 94-9.
34. Alla RK. Dental Materials Science. India:
Jaypee, 2014; 130-5.
35. Banerjee, Avijit, and Timothy F. Watson.
Pickard’s Manual of Operative Dentistry. 9th
ed. New York: Oxford, 2011; 88-95.
36. Powers JM, Wataha JC. Dental Materials:
Properties And Manipulation. 9th ed. USA:
Elsevier, 2008; 285-305.
37. McCabe JF, Walls AWG. Applied dental
materials. 9th ed., Oxford: Blackwell
Publishing., 2008; 13, 196-211.
38. Sakaguchi RL, Powers JM. Craig’s
restorative dental materials. 13th ed.,
Philadelphia: Elsevier, 2012; 91, 161-92.
39. Anusavice KJ. Phillips’ science of dental
materials. 10th ed. Alih Bahasa. Budiman
JA, Purwoko S. Jakarta: EGC, 2004; 54-
61;228-49.
40. Powers, JM. Dental materials properties and
manipulation. 9th ed. Missouri: Mosby Inc,
2008; 32-34;69-92.
41. O’Brien WJ. Dental materials and their
selection. 3rd ed., Illinois: Quintessence
Publishing Co, Inc., 2002; 41, 202-28.
42. Geels K, Fowler DB, Kopp WU. Ruckert M.
Metallographic and materialographic
specimen preparation, light microscopy,
image analysis and hardness testing. 1st ed.,
West Conshohocken: ASTM International.,
2007; 628-32.
43. Lemeshow, Stanley, 1997, Besar Sampel
dalam Penelitian Kesehatan, Gadjah Mada
University, Yogyakarta.
44. Hao Y, Qing L, Hussain M, Yining W,
Effects of bleaching gels on the surface
microhardness of tooth-colored restorative
materials in situ. Journal of Dentistry: 2008;
36(4): 261-7.
45. Ab-Ghani Z, Ooi QQ, and Mohamad D.
Effects of home bleaching on surface
hardness and surface roughness of an
experimental nanocomposite. J Consery
Dent. 2013 Jul-Aug; 16(4): 356–61.
46. Sharafeddin F dan Jamalipor GR. Effects of
35% carbamide peroxide gel on surface
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 10 – 16
16
roughness and hardness of composite resins.
J Dent (Tehran). 2010; 7(1): 6–12.
47. Wu W, McKinney JE. Influence of chemicals
on wear of dental composites. J Dent
Res.1982; 61(10): 1180-3.
48. Taher NM. The effect of bleaching agents on
the surface hardness of tooth colored
restorative materials. J Contemp Dent
Pract.2005; 6(2): 18-26.
49. Mohamad D, Young RJ, Mann AB, Watts
DC. Post-Polymerization of dental resins
composite evaluated with Nanoindentation
and Micro-Raman spectroscopy. Arch
Orofac Sci. 2007; 2: 26–31.
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 17 – 20
17
Regenerasi Tulang pada Kasus Abses Apikalis Kronis
(Laporan Kasus)
Elline
Staf Pengajar Bagian Konservasi Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trsakti
ABSTRACT
Background: Chronic apical abscess cases are often found in dental practice. Chronic apical abscess
is defined as an inflammatory response to pulpal infection and necrosis identified by stepwise onset,
causing almost no discomfort, and characterized by the discontinuous release of pus through a related
sinus tract. Radiographically, there are regularly indications of bone destruction. The source of
infection in the root canal is eradicated by root canal treatment. The main purpose of endodontic
treatment is to finish debridement of the pulp tissue from the canal, combined with shaping and
sufficient obturation of the root canal system. Objective: This case report was written to bring
forward the proper management of tooth with chronic apical abscess and reveal self-bone
regeneration after treatment. Case report: A 27-year-old woman complained of cavity on her left
lower back tooth. There was a history of fistula which appear frequently in the gum near the cavity
tooth. Radiographic examination showed that caries has reached the pulp with periapical lesion and
bone destruction. The canals were prepared with ProTaper Next file with irrigation using 5,25%
sodium hypochlorite, EDTA 17% and chlorhexidine gluconate 2%. Calcium hydroxide paste was
used as an intracanal medicament, then the canals were obtured with continous wave compaction
technique. Four months follow up was advised and healing of periapical lesion with bone regeneration
is evident. Conclusion: Adequate root canal treatment can result in healing of periapical lesions and
bone regeneration on chronic apical abscess.
Keyword: bone regeneration, bone destruction, periapical lesion, endodontic treatment
PENDAHULUAN
Lesi periapikal adalah kondisi patologis
yang umum terjadi pada jaringan periapikal.1
Lebih dari 90 % lesi periapikal dapat
dikategorikan sebagai granuloma, kista radikuler
atau abses.2 Abses bisa terjadi pada 28,7% -
70,07% kasus.3 Abses periapikal bisa
dikategorikan menjadi akut dan kronis. Apses
apikalis kronis merupakan respon peradangan
pada infeksi pulpa dan biasanya gigi telah
nekrosis, seringkali tidak memberikan keluhan
dan adanya pus di jalur sinus tract.
Pada kasus abses apikalis, seringkali
secara radiograf terlihat kerusakan tulang dan
terlihat suatu gambaran radiolusensi.4 Secara
umum, adanya suatu sinus tract pada mukosa
rongga mulut menunujukkan kondisi nekrosis
pada pulpa gigi, supuratif (pus) pada daerah
periapikal atau kerusakan jaringan periodontal
dari gigi. Kerusakan periodontal dapat
menyebabkan suatu resorbsi dari tulang
periapikal daerah kortikal bukal atau lingual dan
mukoperiostium, sehingga drainase pus yang
timbul mencapai permukaan mukosa daerah
permukaan.5 Periodontitis apikalis terinduksi
oleh mikroorganisme dalam saluran akar dan
terjadilah suatu inflamasi di apikal gigi.
Inflamasi bisa terjadi secara lokal, kemudian
terjadi resorbsi jaringan keras sampai terjadi
destruksi jaringan periapikal .6
Proses mengeliminasi mikroorganisme
dalam sistem saluran akar penting untuk
dilakukan. Tujuan utama dari perawatan saluran
akar adalah mengeliminasi jaringan vital ataupun
nekrosis dari pulpa terinfeksi sehingga terjadi
suatu proses penyembuhan. Proses pembersihan
dan disinfeksi yang optimum pada saluran akar
dapat menghasilkan proses penyembuhan yang
lebih cepat.7 Perawatan endodontik berfungsi
untuk membuang seluruh debridemen jaringan
pulpa dari saluran akar, dikombinasikan dengan
pembentukkan saluran akar sampai tahapan
obturasi yang baik pada sistem saluran akar.
Laporan kasus ini diharapkan dapat
menambah informasi tentang tatalaksana gigi
dengan abses apikalis kronis disertai
penyembuhan tulang setelah dilakukan
perawatan
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 17 – 20
18
LAPORAN KASUS
Kasus
Regenerasi tulang pada gigi dengan abses
apikalis kronis
Seorang perempuan usia 27 tahun datang
dengan keluhan pada gigi 36. Gigi tidak pernah
dilakukan perawatan sebelumnya, dan pernah
mengalami sakit spontan 1 tahun lalu. Pada
anamnesis diketahui bahwa pernah ada suatu
sinus tract yang hilang timbul pada daerah gusi.
Pada pemeriksaan ekstra oral tidak ada simptom.
Pemeriksaan intra oral menunjukkan adanya lesi
karies dalam pada disto-oklusal mencapai pulpa.
Terlihat juga adanya sinus tract pada gusi sekitar
gigi 36.
Tes dingin dan Electric pulp tester
menunjukkan hasil negatif, dan tidak ada sensitif
terhadap perkusi dan palpasi. Pada pemeriksaan
radiografi menunujukkan bahwa karies telah
mencapai pulpa disertai lesi periapikal
dankerusakan tulang pada gigi 36. Diagnosis gigi
36 adalah abses apikalis kronis et causa nekrosis
pulpa (Gambar 1 dan 2).
Gambar 1. Radiograf 36 Gambar 2. Klinis 36
Perawatan saluran akar dilakukan pada
gigi 36. Gigi diisolasi menggunakan rubber dam,
pembuatan artificial wall, preparasi akses
kavitas, dan ditemukan 3 saluran akar, yaitu
mesiobukal, mesiolingual, dan distal. Eksplorasi
saluran akar menggunakan jarum K-files #8, #10,
dan dilakukan irigasi. Panjang kerja ditentukkan
menggunakan elektronik apex locator (Root ZX,
Morita), dan dikonfirmasi menggunakan foto
radiograf. Apical glide ditentukkan
menggunakan file Proglider (Dentsply).
Preparasi biomekanis saluran akar
dilakukan menggunakan ProTaper Next
Rotary System (Dentsply) menggunakan teknik
single length. Saluran akar diirigasi dengan
NaOCl pada saat instrumentasi. Saluran
mesiobukal dan mesolingual diselesaikan sampai
file X2, dan distal X3.
Gambar 3. Gigi pasca preparasi biomekanis
Medikamen intrakanal diberikan selama 1
minggu menggunakan Kalsium Hidroksida
(Ultracal, Ultradent) dan pasien diinstruksikan
kembali 1 minggu.
Setelah 1 minggu, pasien kembali tanpa
keluhan. Pada pemeriksaan intraoral sinus tract
telah hilang . Pemeriksaan perkusi dan palpasi
menunjukkan hasil negatif. Setelah itu dilakukan
pemasangan rubber dam dan gigi diobturasi
menggunakan guttaperca. Teknik obturasi yang
digunakan adalah teknik continous wave
compaction menggunakan sealer (Sealapex,
Sybron Endo), guttaperca dipotong di bawah 2
mm di bawah orifice dan diberikan barrier
semen ionomer kaca dan diberikan tumpatan
sementara (Gambar 4)
Gambar 4. Hasil obturasi ggi 36
Setelah 1 minggu pemeriksaan ekstra oral
dan intraoral tidak ada keluhan dan dilakukan
restorasi final berupa porselin fusi metal disertai
penggunaan pasak fiber. Setelah ontrol 4 bulan
menunjukkan adanya penyembuhan lesi
periapikal dan regenerasi tulang.
Gambar 5. Gigi telah direstorasi dan terlihat
regenerasi tulang
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 17 – 20
19
PEMBAHASAN
Abses Apikalis Kronis adalah merupakan
variasi dari periodontitis apikalsi yang
disebabkan oleh infeksi saluran akar dan
mengakibatkan keluarnya pus pada permukaan
gusi. Secara radiograf, kondisi ini terlihat
radiolusen dan dapat terlihat suatu sinus tract ,
dan terlihat suatu jalur drainase abses yang
melalui tulang, periostium dan mukosa .9
Bakteri dan produknya dalam saluran akar
gigi adalah penyebab utama dari mulainya
peradangan periapikal. Pertama, pulpa
mengalami infeksi dan nekrosis. Adanya
hubungan antara pulpa gigi dan jaringan
periapikal menyebabkan suatu infeksi pada
daerah periodontal sehingga menyebabkan lesi
periodontal. Pertahanan dari host tidak dapat
menanggulangi progress dari infeksi karena
sirkulasi yang kurang di daerah tersebut,
sehingga gigi menjadi nekrosis. Adanya iritasi
mengakibatkan adanya respon imun inate dan
adaptif dari jaringan periapical.1 Respon imun
yang lemah membuat ketidakmampuan untuk
menghancurkan bakteri yang tumbuh subur
dalam saluran akar , sehingga tujuan utama dari
perawatan saluran akar adalah untuk
mengeliminasi biofilm , bakteri dan produknya.10
Preparasi biomekanis menggunakan sistem
rotary memiliki keuntungan dalam fleksibilitas
alat yang baik, resisten terhadap cyclic fatigue,
instrument patah. Selain itu, bentuk penampang
jarum cross section rectangular shape di tengah
dan ada 2 titik yang berkontak dengan dinding
saluran akar. Bentuk ini dapat meningkatkan
proses cutting, mengurangi tekanan dan kontak
antara file dan dinding dentin, memaksimalkan
pembuangan debris ke arah koronal.12
Perawatan saluran akar dengan preparasi
biomekanis , irigasi antibakteri dapat mengurangi
bakteri 40 – 60 %.13
Pada kasus ini Kalsium Hidroksida
digunakan untuk menginduksi penyembuhan
daerah periapikal. Medikamen ini memiliki
kemampuan sebagai antimikrobial, anti
inflamasi, mengurangi matriks metalloproteinase
dengan aktvitas alkalin fosfat dan sintesis
kolagen.14 Kalsium Hidroksida memiliki pH 12.5
– 12.8 dan dapat terpecah menjadi ion kalium
dan hidroksil. Ion hidroksi memiliki ph alkali
sehingga dapat menghancurkan membrane
sitoplasma bakteri, dan menghancukan
proteinnya.15 Souza dkk mengatakan bahwa
penggunaan kalsium hidroksida pada perawatan
endodontik dapat meningkatkan keberhasilan
perawatan lesi periapical.16
Proses penyembuhan periapikal adalah
dengan terbentuknya jaringan lunak dan keras.17
Formasi pembentukan tulang dan sementum
terbentuk jika proses peradangan apikal hilang
karena pada proses penyembuhan sel
osteoprogenitor atau sel mesenkim dari sumsum
tulang, sehingga terjadi proliferasi dan
diferensiasi sel odontoblas dan pembentukkan
matriks tulang 17. BMPs (Bone Morphogenic
Proteins) mensimulasi sel Osteoprogenitor
(OPG) untuk menjadi sel OPG. Sel
Osteoprogenitor (OPG) menarik growth factors
secara kemotaktik. termasuk epidermal growth
factor (EGF), insulin-like growth factor (IGF),
TGFß, dan PDGF, menyebabkan terjadinya
proliferasi. BMPs menyebabkan diferensiasi
akhir dari sel OPG menjadi cuboidal,
bermetabolisme menjadi osteoblast aktif pada
permukaan tulang dan menghasilkan osteoid
yang akan teremineralisasi dan membentuk
tulang.18
KESIMPULAN
Perawatan saluran akar yang adekuat dapat
menyembuhkan lesi periapikal dan menginduksi
regenerasi tulang pada kasus abses apikalis
kronis.
DAFTAR PUSTAKA
1. Karunakaran JV, Abraham CS, Karthik AK
JN. Successful nonsurgical management of
periapical lesions of endodontic origin: A
conservative orthograde approach. J Pharm
Bioallied Sci. 2017;9(5):246-251.
2. Lalonde ER, Leubke RG. The frequency and
distribution of periapical cysts and
granuloma. Oral Surg Oral Med Oral Pathol.
1986;25:861-868.
3. Schulz M, von Arx T, Altermatt HJ,
Bosshardt D. Histology of periapical lesions
obtained during apical surgery. J Endod.
2009;35:634,642.
4. Berman LH, Rotstein I. Diagnosis. In:
Hargreaves K, ed. In Cohen’s Pathways of the
Pulp. 11th ed. Missouri: Elsevier; 2016:30.
5. Tai TF, Huang SH, Lin CP, Tsai YL, Jeng
JH. Sinus tracts from proximal roots with
infected root canals ── cases report. J Dent
Sci. 2006;1(4):2-6.
6. Croitoru IC, Craitoiu S, Petcu CM, et al.
Clinical, imagistic and histopathological
study of chronic apical periodontitis. Rom J
Morphol Embryol. 2016;57(2):719-728.
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 17 – 20
20
7. Sigurdsson A, Garland RW, Le KT, Woo SM.
12-month Healing Rates after Endodontic
Therapy Using the Novel GentleWave
System : A Prospective Multicenter Clinical
Study. J Endod. 2016;42(7):1040-1048.
8. Gupta R, Hasselgren G. Prevalence of
Odontogenic Sinus Tracts in Patients
Referred for Endodontic Therapy. J Endod.
2003;29(12):12-14.
9. Ricucci D, Loghin S, Gonc LS.
Histobacteriologic Conditions of the Apical
Root Canal System and Periapical Tissues in
Teeth Associated with Sinus Tracts. 2017:1-9.
10. Cohenca N, Amaro A. Root Canal Infection
and Endodontic Disease. In: Disinfection of
Root Canal Systems: The Treatment of Apical
Periodontitis: The treatment of apical
periodontitis. Wiley Blackwell;2014.
11. Chandrasekhar P, Shetty RU, Adlakha T,
Shende S, Podar R. A comparison of two
NiTi rotary systems , ProTaper Next and Silk
for root canal cleaning ability ( An in vitro
study ). Indian J Conserv endod.
2016;1(1):22-24.
12. Ruddle C, Machtou P, West J. The shaping
movement: fifth-generation technology. Dent
today. 2013;32:6-9.
13. Sathorn C, Parashos P, Messer HH.
Effectiveness of single- versus multiple-visit
endodontic treatment of teeth with apical
periodontitis : a systematic review and. J Int
Endod. 2005:347-355.
14. Bezerra da Silva LA, Bezerra da Silva RA,
Nelson-Filho P, Cohenca N. Intracanal
medication in root canal disinfection. In:
Nestor Cohenca, ed. Disinfection of Root
Canal Systems: The Treatment of Apical
Periodontitis. Wiley Blackwell; 2014:252-
253.
15. Dohyun K, Euiseong K. Antimicrobial effect
of calcium hydroxide as an intracanal
medicament in root canal treatment : a
literature review - Part II . in vivo studies.
Rest Dent Endod. 2015;7658:97-103.
16. Broon NJ, Bortoluzzi EA, Bramante CM.
Repair of large periapical radiolucent lesions
of endodontic origin without surgical
treatment. J Aust Endod. 2007;33:36-41.
17. Lin ML, Huang GTJ. Pathobiology of apical
periodontitis. In: Cohen’s Pathways of the
Pulp. 11th ed. Missouri: Elsevier; 2016:652-
655.
18. Metzger Z, Kfir A. Healing of apical lesions:
How do they heal, why does the healing take
so long, and why do some lesions fail to heal?
In: Nestor Cohenca, ed. Disinfection of Root
Canal Systems: The Treatment of Apical
Periodontitis. Wiley Blackwell; 2014:303-
305.
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 21 – 27
21
Hubungan Antara Gigi Berjejal Dan Gingivitis
(Laporan Penelitian)
Lies Zubardiah1, Marilyn Octavia2 1 Staf Pengajar Bagian Periodonti Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti 2 Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti
ABSTRACT
Background: Gingivitis is inflammation of the gingiva which is characterized by changes in the
gingiva such as redness, udematous, swelling, loss of stippling, and bleeding. The main cause of
gingivitis is bacterial plaque that accumulates in the gingival sulcus. Crowded teeth facilitate the
accumulation of plaque because makes it difficult for oral hygiene techniques. Objective: To find out
the relationship between crowded teeth with gingivitis in patients who came to the Dental and Oral
Hospital of the Faculty of Dentistry, Trisakti University. Method: Observational analytic study with
cross sectonal design using 72 subjects aged between 13-50 years. The subjects were divided into 2
groups consisted of 36 patients with crowded teeth and 36 without crowded teeth. The condition of the
teeth was recorded, and PBI was examined. Results: Pearson Chi-Square correlation test showed a
significant relationship between age (group 43-48.9 years) with gingivitis (p <0.05). The relationship
between crowded teeth and gingivitis showed no significant relationship (p> 0.05). For the relationship
between the amount of jaw involvement in crowded teeth and gingivitis, there was a significant
relationship (p <0.05). Conclusion: There is a significant relationship between crowded teeth and
gingivitis in certain age groups.
Keyword: gingivitis, crowded teeth, Papilla Bleeding Index
PENDAHULUAN
Gingivitis merupakan peradangan pada
gingiva tanpa kehilangan perlekatan periodontal.1
Hal ini ditandai dengan adanya perubahan warna
gingiva mulai dari merah, merah kebiruan, hingga
biru, ukuran gingiva menjadi besar, kontur
marginal membulat, konsistensi lunak dan
udematus ataupun menjadi keras dan fibrosis.
Terjadi perubahan tekstur yang ditandai dengan
berkurangnya stipling hingga hilang sama sekali,
dan mudah berdarah pada probing.2 Gingivitis
pada dasarnya disebabkan oleh bakteri yang
terdapat pada plak. Akumulasi plak dapat terjadi
karena kebersihan mulut yang buruk, restorasi
yang tidak baik, dan posisi gigi yang tidak
teratur.3
Untuk mencegah gingivitis, diperlukan
ketekunan dalam membersihkan gigi dan mulut.
Menjaga kesehatan gingiva sama pentingnya
seperti menjaga kesehatan gigi. Masyarakat
Indonesia seringkali masih belum sadar akan
pentingnyagigi dan gusi, sehingga dapat
dibuktikan dari hasil Laporan Survei Kesehatan
Rumah Tangga (SKRT) Depkes RI tahun 2011,
yang menyatakan 60% masyarakat Indonesia
mengidap penyakit periodontal. 4
Gigi berjejal merupakan bentuk maloklusi
yang sering dijumpai. Gigi berjejal adalah akibat
ketidakseimbangan hubungan antara ukuran gigi
dengan ukuran rahang sehingga menyebabkan
gigi berputar, bergeser dan bertumpuk. Nance
(1947) mengemukakan bahwa gigi berjejal dapat
terjadi karena ketidaksesuaian antara ruangan
yang diperlukan dengan ruangan yang tersedia
dalam lengkung rahang.5 Gigi berjejal belum
dapat diketahui penyebabnya dengan pasti. Gigi
berjejal diyakini erat hubungannya dengan
perkembangan evolusi manusia yaitu terdapat
pengurangan ukuran rahang tanpa diimbangi
dengan pengurangan ukuran gigi dan jumlah
gigi.6 Gigi berjejal secara estetik mengganggu
penampilan, dan secara fungsional menimbulkan
kesulitan dalam pembersihan gigi. Kesulitan ini
jika terus menerus dibiarkan dapat mendorong
retensi plak pada margin gingiva dan
mengakibatkan peradangan gingiva atau
gingivitis.7
Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan di University of Penambuco, Brazil
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 21 – 27
22
(2011), menunjukkan bahwa 100% subyek
dengan gigi berjejal memiliki gingiva yang
berdarah saat dilakukan probing.8 Begitu juga
pada penelitian di Universidade da Regiao de
Joinville Brazil (2004), menunjukkan bahwa
100% subyek dengan gigi berjejal juga disertai
gingivitis dengan derajat keparahan yang
bervariasi.9
Gambar 1. Gigi berjejal pada RA dan RB.
Gingiva yang sehat berwarna merah muda,
konsistensi kenyal, tekstur berbintik-bintik seperti
kulit jeruk (stipling), tepi meruncing, dan tidak
mudah berdarah. Gingiva yang sehat dapat
mengalami peradangan yang disebut gingivitis.
Gingivitis merupakan salah satu bentuk penyakit
periodontal yang paling sering dijumpai.
Peradangan pada gingiva dapat dilihat
berdasarkan adanya perubahan pada warna,
konsistensi, tekstur, ukuran, dan kontur.11
Peradangan gingiva dimulai ketika plak
melekat di daerah interdental, kemudian
peradangan dapat meluas ke marginal gingiva.
Pembuluh darah yang mengalami dilatasi
menyebabkan gingiva berwarna merah dan
udematus disertai eksudat gingiva. Tepi gingiva
membulat, interdental groove menghilang dan
konsistensi gingiva menjadi lunak, mengkilap
serta stipling berkurang hingga menghilang. Jika
iritasi plak berlangsung lama, maka konsistensi
gingiva akan mengeras dan bentuk gingiva
menjadi tidak beraturan. Keluhan utama pada
pasien gingivitis adalah gingiva mudah berdarah
ketika menyikat gigi dan ketika makan makanan
yang keras. Gingiva yang mengalami peradangan
juga mudah berdarah ketika dilakukan
pemeriksaan dengan probing.11 Pasien gingivitis
sering mengalami halitosis atau bau mulut yang
disebabkan oleh aroma darah dan buruknya oral
hygiene. 10
Penyebab utama gingivitis adalah plak
bakteri yang berada pada supragingiva dan
subgingiva. Bakteri yang berperan pada gingivitis
terdiri atas spesies Gram positif 56% seperti
Streptococcus sanguinis dan Actinomyces
viscosus. Bakteri Gram negatif 44% seperti
Fusobacterium nucleatum dan Prevotella
intermedia, Spesies fakultatif 59% dan spesies
anaerob 41%.7 Faktor predisposisi merupakan
faktor yang memudahkan akumulasi plak seperti
restorasi yang salah, karies, impaksi makanan,
gigi tiruan, alat ortodonti yang tidak adekuat, gigi
berjejal, bernapas melalui mulut, developmental
groove pada permukaan servikal, dan kebiasaan
merokok.8 Gingivitis juga dapat dipengaruhi atau
diperberat oleh faktor penyakit dan kondisi
sistemik, seperti penggunaan obat-obatan,
malnutrisi, kelainan sistem endokrin, hormonal,
dan kelainan darah. Tingkat keparahan gingivitis
dapat diukur dengan Papilla Bleeding Index (PBI)
yang diperkenalkan oleh Saxer dan Muhlemann
(1975). 9
Perawatan gingivitis pada gigi berjejal
dimulai dengan pembuangan semua iritan lokal
penyebab radang dengan skeling dan penghalusan
akar (SPA) serta kontrol plak. Faktor predisposisi
yang memudahkan akumulasi plak juga
dihilangkan. Jika setelah dievaluasai tanda-tanda
peradangan belum hilang dan poket masih dalam,
maka dilakukan pembuangan dinding jaringan
lunak poket yang patologis dengan tindakan
bedah. 10
Pada penelitian ini ingin diketahui
bagaimana hubungan antara gigi berjejal dengan
gingivitis pada subyek yang datang ke Rumah
Sakit Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi
Universitas Trisakti. Hingga saat ini penelitian
mengenai hubungan antara gigi berjejal dengan
gingivitis kurang dikembangkan di Indonesia.
Pada penelitian ini juga ingin dilihat distribusi
frekuensi subyek gingivitis yang disebabkan oleh
gigi berjejal.
METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah observasional
analitik dengan rancangan potong silang untuk
melihat adanya hubungan antara gigi berjejal
dengan gingivitis. Subyek adalah pasien yang
datang ke Rumah Sakit Gigi dan Mulut Fakultas
Kedokteran Gigi Universitas Trisakti (RSGM
FKG Usakti) yang berusia 13 hingga 50 tahun
pada bulan Oktober hingga Desember 2014.
Subyek sebanyak 72 terdiri dari laki-laki dan
perempuan dibagi dalam 2 kelompok yaitu 36
disertai gigi berjejal dan 36 tidak disertai gigi
berjejal.
Subyek yang tidak termasuk dalam kriteria
inklusi adalah pasien dengan kondisi sangat
lemah; pasien yang menderita penyakit sistemik
seperti diabetes melitus, kelainan darah, penyakit
kardiovaskular, epilepsi, dan lupus; pasien yang
sedang mengonsumsi obat-obatan anti konvulsan,
imunosupresan, calcium channel blocker;
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 21 – 27
23
pengguna alat ortodonti; memiliki restorasi gigi
yang mengemper; wanita yang sedang hamil dan
menstruasi.
Alat dan bahan yang digunakan adalah alat
standar pemeriksaan, prob WHO, nierbekken,
kamera, alat tulis, penggaris, berbagai formulir
(informed consent, data pasien, hasil penelitian),
masker, sarung tangan, cutton bud, larutan
pewarna, alkohol 70%, povidone iodine 10%.
Subyek diminta kesediaannya untuk
berpartisipasi dalam penelitian. Gigi-geligi dan
kondisi gingiva dicatat meliputi warna, ukuran,
kontur, tekstur, dan konsistensi. Dilakukan
pemeriksaan indeks PBI dan data dianalisis
menggunakan program Statistical Product and
Service Solution (SPSS) versi 20.0 dan Microsoft
Word 2007.
HASIL
Subyek sebanyak 72 orang terdiri atas 36
subyek gigi berjejal dan 36 tanpa gigi berjejal.
Berdasarkan jenis kelamin subyek pria sebanyak
38 orang (52,8%) dan wanita 34 orang (47,2%).
Berdasarkan kelompok usia, subyek terbanyak
pada kelompok usia 25 – 30,9 tahun (23 orang/
31,9%) dan terkecil pada kelompok usia 49 – 54
tahun (1 orang/2,8%). Gigi berjejal dibagi 2
berdasarkan kedudukannya yaitu gigi berjejal
pada 1 rahang dan gigi berjejal pada 2 rahang.
Gigi berjejal pada 1 rahang dibagi menjadi gigi
berjejal hanya di rahang atas (RA) dan gigi
berjejal hanya di rahang bawah (RB). Subjek gigi
berjejal, lebih banyak pada kedua rahang yaitu 22
orang (61,1%). Subyek dengan gigi berjejal hanya
pada 1 rahang paling banyak pada RB yaitu 9
orang (25%).
Dari hubungan antara jenis kelamin dengan
kedudukan gigi (berjejal/ tidak berjejal), pada 36
subyek tanpa gigi berjejal terbanyak pada pria (21
orang/ 58,3%), gigi berjejal pada 1 rahang
terbanyak pada wanita, baik di RA (3 orang/
8,3%) maupun di RB (5 orang/ 13,9%). Pria dan
wanita memiliki gigi berjejal pada 2 rahang, sama
banyak yaitu 11 orang (30,6%). Dari hubungan
antara usia dengan kedudukan gigi (berjejal/tidak
berjejal), subyek tanpa gigi berjejal terbanyak
pada kelompok usia 25 – 30,9 tahun yaitu 10
orang (27,8%). Subyek dengan gigi berjejal 1
rahang terbanyak pada kelompok usia 25 – 30,9
tahun baik pada RA maupun RB 2 orang (5,6%)
dan 4 orang (11,1%). Subyek dengan gigi berjejal
pada kedua rahang terbanyak pada kelompok usia
25 – 30,9 tahun dan 31 – 36,9 tahun yaitu masing-
masing 7 orang (19,4%).
Dari hubungan antara jenis kelamin dengan
Papilla Bleeding Index (PBI) pada subyek tanpa
gigi berjejal. Pada pria, PBI terbesar (2-2,99)
ditemukan 12 orang (33,3%). Pada wanita PBI
terbesar ada pada 2 kelompok yaitu kelompok PBI
1-1,99 dan 2-2,99 sebanyak 6 orang (16,7%).
(Tabel 1)
Tabel 1. Hubungan antara jenis kelamin dengan PBI
pada subyek tanpa gigi berjejal
Jenis Kelamin
PBI
Total 0 –
0,99
1 –
1,99
2 –
2,99 3 - 4
Pria Jumlah 2 7 12 0 21
Persentase
(%) 5,6% 19,4% 33,3% 0% 58,3%
Wanita Jumlah 2 6 6 1 15
Persentase
(%) 5,6% 16,7% 16,7% 2,8% 41,7%
Total Jumlah 36
Persentase
(%) 100%
.
Dari hubungan antara jenis kelamin dengan
PBI pada subyek dengan gigi berjejal. Pada pria,
PBI terbesar (2-2,99) sebanyak 8 orang (22,2%).
Pada wanita PBI terbesar (2-2,99) sebanyak 10
orang (27,8%). (Tabel 2)
Tabel 2. Hubungan antara jenis kelamin dengan PBI
pada subyek dengan gigi berjejal.
Jenis Kelamin
PBI
Total 0 –
0,99
1 –
1,99
2 –
2,99 3 - 4
Pria Jumlah 0 6 8 3 17
Persentase
(%) 0% 16,7% 22,2% 8,3% 47,2%
Wanita Jumlah 2 5 10 2 19
Persentase
(%)
5,6% 13,9% 27,8% 5,6% 52,8%
Total Jumlah 36
Persentase
(%) 100%
Dari hubungan antara usia dengan PBI pada
subyek tanpa gigi berjejal, subyek pada kelompok
usia 19 - 24,9 tahun dengan nilai PBI 2-2,99
merupakan yang terbanyak yaitu 7 orang (19,4%),
diikuti dengan kelompok usia 37 – 42,9 tahun,
dengan nilai PBI 2-2,99 sebanyak 6 orang
(16,7%).setelah itu diikuti oleh subyek pada
kelompok usia 31 – 36,9 tahun, dengan nilai PBI
2-2,99 sebanyak 4 orang (11,1%). (Tabel 3)
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 21 – 27
24
Tabel 3. Hubungan antara usia dengan PBI pada
subyek tanpa gigi berjejal.
Usia (tahun)
PBI
Total 0 –
0,99
1 –
1,99
2 –
2,99 3 - 4
13 – 18,9 Jumlah
4 0 0 0 4
Persentase
(%) 11,1% 0% 0% 0% 11,1%
19 – 24,9 Jumlah
0 2 7 0 9
Persentase
(%) 0% 5,6% 19,4% 0% 25%
25 – 30,9 Jumlah
0 9 1 0 10
Persentase
(%) 0% 25% 2,8% 0% 27,8%
31 – 36,9 Jumlah
0 0 4 1 5
Persentase
(%) 0% 0% 11,1% 2,8% 13,9%
37 – 42,9 Jumlah
0 1 6 0 7
Persentase
(%) 0% 2,8% 16,7% 0% 19,4%
43 – 48,9 Jumlah
0 1 0 0 1
Persentase
(%) 0% 2,8% 0% 0% 2,8%
49 – 54 Jumlah
0 0 0 0 0
Persentase
(%) 0% 0% 0% 0% 0%
Total Jumlah 36
Persentase
(%) 100%
Dari hubungan antara usia dengan PBI pada
subyek tanpa gigi berjejal, ditemukan pada
kelompok usia 25 - 30,9 tahun dengan PBI 2-2,99
terbesar sebanyak 9 orang (25%). Kemudian
diikuti dengan kelompok usia 31 – 36,9 tahun,
dengan PBI 2-2,99 sebanyak 6 orang (16,7%).
(Tabel 4)
Tabel 4. Hubungan antara usia dengan PBI pada
subyek dengan gigi berjejal.
Usia (tahun)
PBI
Total 0 –
0,99
1 –
1,99
2 –
2,99 3 - 4
13 – 18,9 Jumlah
0 2 1 0 3
Persentase
(%) 0% 5,6% 2,8% 0% 8,3%
19 – 24,9 Jumlah
0 5 1 1 7
Persentase
(%) 0% 13,9% 2,8% 2,8% 19,4%
25 – 30,9 Jumlah
0 2 9 2 13
Persentase
(%) 0% 5,6% 25% 5,6% 36,1%
31 – 36,9 Jumlah
0 0 6 1 7
Persentase
(%) 0% 0% 16,7% 2,8% 19,4%
37 – 42,9 Jumlah
1 1 1 1 4
Persentase
(%) 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 11,1%
43 – 48,9 Jumlah
0 1 0 0 1
Persentase
(%) 0% 2,8% 0% 0% 2,8%
49 – 54 Jumlah
1 0 0 0 1
Persentase
(%) 2,8% 0% 0% 0% 2,8%
Total Jumlah 36
Persentase
(%) 100%
Pada subyek dengan gigi berjejal maupun
tanpa gigi berjejal. umumnya memiliki PBI 2-2,99
yaitu sebanyak 18 orang (25%). Dari 14 subyek
dengan gigi berjejal, sebanyak 4 orang memiliki
gigi berjejal hanya pada RA dengan PBI 1-1,99
(28,5%). Subyek dengan gigi berjejal hanya pada
rahang bawah ditemukan sebanyak 5 orang
dengan PBI 2-2,99 (35,7%). Dari 22 subyek
dengan gigi berjejal pada kedua rahang, 13 orang
memiliki PBI 2-2,99 (59,1%).
PEMBAHASAN
Beberapa studi yang telah dilakukan,
menunjukkan pasien dengan gigi berjejal
umumnya disertai gingivitis dengan derajat
keparahan yang bervariasi.8,9 Schroeder (2004)
membuktikan ada hubungan langsung antara
bakteri plak dengan peradangan gingiva. Namun,
dengan adanya oral hygiene yang baik gingivitis
tidak akan berkembang meskipun gigi berjejal.9
Derajat keparahan gingivitis dapat ditentukan
dengan pemeriksaan PBI. Jika hasil skor 0-0,99
berarti kondisi gingiva secara klinis sehat; 1-1,99
gingivitis ringan; 2-2,99 gingivitis sedang; dan 3-
4 gingivitis berat.11
Jumlah pasien yang datang di RSGM FKG
Usakti lebih banyak pria daripada wanita. Hal ini
menunjukkan kemungkinan pria memiliki
masalah kesehatan gigi dan mulut yang lebih
besar sehingga menimbulkan keluhan yang dirasa
harus mendapatkan perawatan di rumah sakit.
Sebagian besar pasien yang datang, terdapat pada
kelompok usia 25 – 30,9 tahun. Hal ini
menunjukkan pada usia tersebut rentan terkena
penyakit gigi dan mulut.
Dari 36 pasien dengan gigi berjejal,
sebagian besar memiliki gigi berjejal pada kedua
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 21 – 27
25
rahang. Kemungkinan karena ketidaksesuaian
antara ruangan yang diperlukan dengan ruangan
yang tersedia berada pada kedua lengkung
rahang.12 Dari 14 pasien yang memiliki gigi
berjejal hanya pada 1 rahang, sebagian besar
terdapat pada rahang bawah. Penyebabnya selain
ketidakseimbangan antara ukuran rahang dan
gigi-geligi, kemungkinan ada faktor muskular
yang berpengaruh seperti keseimbangan tekanan
dari lidah, pipi dan bibir.13
Gigi berjejal lebih banyak pada wanita
karena pria sebagian besar memiliki lengkung
rahang yang lebih besar dibandingkan wanita.14
Dari hasil uji korelasi Pearson Chi-Square untuk
hubungan antara jenis kelamin dengan gigi
berjejal didapat nilai p=0,345 (p>0,05) yang
menunjukkan tidak ada hubungan bermakna
antara jenis kelamin dengan gigi berjejal.
Berdasarkan dari hasil uji korelasi Pearson Chi-
Square untuk hubungan antara usia dengan gigi
berjejal menunjukkan tidak ada hubungan
bermakna yang didapat dengan nilai p=0,817
(p>0,05). Pasien pria yang datang sebagian besar
terkena gingivitis (derajat sedang) baik pada pria
tanpa gigi berjejal maupun dengan gigi berjejal.
Pria tanpa gigi berjejal dengan gingivitis,
jumlahnya lebih banyak daripada pria dengan gigi
berjejal. Pria dengan gigi berjejal kemungkinan
menyadari akan giginya yang berjejal sehingga ia
berusaha untuk meningkatkan kebersihan
mulutnya.
Pasien wanita yang datang baik tanpa gigi
berjejal maupun dengan gigi berjejal sebagian
besar terkena gingivitis (derajat sedang). Wanita
dengan gigi berjejal yang terkena gingivitis,
jumlahnya lebih banyak daripada wanita tanpa
gigi berjejal. Wanita dengan gigi berjejal
kemungkinan kurang seksama dalam melakukan
oral hygiene karena kesibukannya dalam
mengurus rumah tangga. Dari hasil uji korelasi
Pearson Chi-Square untuk hubungan antara jenis
kelamin dengan gingivitis didapat nilai p=0,787
(p>0,05) yang menunjukkan tidak ada hubungan
bermakna antara jenis kelamin dengan gingivitis.
Pada kelompok usia 13 – 18,9 tahun tanpa
gigi berjejal sebagian besar memiliki gingiva
sehat, sedangkan pada kelompok usia yang sama
dengan gigi berjejal umumnya terkena gingivitis
ringan. Kemungkinan pasien pada kelompok ini
masih berusia muda sehingga masih kurang
kesabaran dalam membersihkan gigi-geliginya.
Pada kelompok usia 19 – 24,9 tahun tanpa gigi
berjejal umumnya terkena gingivitis sedang,
sedangkan pada kelompok usia yang sama dengan
gigi berjejal umumnya terkena gingivitis ringan.
Kemungkinan pasien pada kelompok usia ini
dengan gigi berjejal menyadari akan giginya yang
berjejal sehingga ia berusaha untuk meningkatkan
kebersihan mulutnya.
Pada kelompok usia 25 – 30,9 tahun tanpa
gigi berjejal sebagian besar terkena gingivitis
ringan, sedangkan pada kelompok usia yang sama
dengan gigi berjejal terkena gingivitis sedang.
Kemungkinan pasien pada usia ini berada pada
kelompok usia aktif sehingga kekurangan waktu
untuk memperhatikan kesehatan rongga
mulutnya. Pada kelompok usia 31 – 36,9 tahun
tanpa gigi berjejal dan dengan gigi berjejal
umumnya terkena gingivitis (derajat sedang).
Pasien dengan gigi berjejal yang terkena gingivitis
jumlahnya lebih banyak daripada pasien tanpa
gigi berjejal. Kemungkinan pasien pada
kelompok usia 31 – 36,9 tahun memiliki stres
emosional yang tinggi. Pada penelitian ini, stres
emosional pada usia awal dewasa kemungkinan
terjadi ketika seseorang kesulitan mendapatkan
pekerjaan ataupun kesulitan di bidang ekonomi
ataupun kesulitan dalam menyeimbangkan
hidupnya baik bekerja, berumah tangga, dan
mengurus keluarga.17,18
Stres emosional dapat memicu terjadinya
penyakit periodontal. Stres dan depresi dapat
menurunkan fungsi sistem imun dan
memfasilitasi respon inflamasi. Penurunan sistem
imun dimediasi oleh kelenjar hipotalamus,
pituitari, dan adrenal. Kortisol dibentuk sehingga
menurunkan sistem imun dengan cara
menghambat immunoglobulin A dan G serta
fungsi neutrofil. Hal ini menyebabkan
meningkatnya kolonisasi biofilm dan
menurunkan kemampuan tubuh melawan invasi
bakteri.19
Pada kelompok usia 37 – 42,9 tahun tanpa
gigi berjejal umumnya terkena gingivitis sedang,
sedangkan pada kelompok usia yang sama dengan
gigi berjejal memiliki jumlah yang sama untuk
gingiva sehat, gingivitis ringan, sedang dan berat.
Hal ini menunjukkan kesehatan gingiva
ditentukan dari tingkat oral hygiene setiap
individu. Apabila tingkat oral hygiene sangat
baik, maka gingiva akan sehat. Apabila tingkat
oral hygiene sangat buruk, maka ditemukan
gingivitis.
Pada kelompok usia 43 – 48.9 tahun tanpa
gigi berjejal dan dengan gigi berjejal umumnya
terkena gingivitis (derajat ringan). Pasien pada
kelompok usia 43 – 48.9 tahun kemungkinan lebih
banyak pengetahuan mengenai pemeliharaan
kebersihan gigi dan mulut dibandingkan usia yang
lebih muda sehingga baik pasien tanpa gigi
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 21 – 27
26
berjejal maupun dengan gigi berjejal memiliki
inflamasi gingiva yang lebih ringan jika
dibandingkan pada kelompok usia yang lain. Dari
hasil uji korelasi Pearson Chi-Square untuk
hubungan antara usia dengan gingivitis didapat
nilai p=0 (p<0,05) yang menunjukkan ada
hubungan bermakna antara usia dengan gingivitis.
Pasien dengan gigi berjejal maupun tanpa
gigi berjejal umumnya terkena gingivitis sedang.
Hal ini disebabkan karena rata-rata pasien yang
datang ke RSGM FKG Usakti tergolong dalam
sosio-ekonomi menengah ke bawah, yang
menyebabkan kurangnya pengetahuan akan
melakukan oral hygiene dengan baik. Hal ini
ditandai baik pasien yang memiliki gigi berjejal
dan tidak berjejal, banyak disertai karies, plak dan
kalkulus.
Beberapa pasien juga diduga memiliki
periodontitis kronis lokal baik pada pasien dengan
gigi berjejal maupun tidak berjejal. Hal ini
ditandai dengan adanya tanda-tanda klinis seperti
gingivitis, plak dan kalkulus yang terasa saat
dilakukan probing di subgingiva, perdarahan yang
spontan saat probing, dan dirasakan ada
kegoyangan pada gigi. Oleh karena itu, dari hasil
uji korelasi Pearson Chi-Square untuk hubungan
antara gigi berjejal dengan gingivitis
menunjukkan tidak ada hubungan bermakna yang
didapat dari nilai p=0,321 (p>0,05).
Pasien dengan gigi berjejal pada 1 rahang
umumnya terkena gingivitis ringan, sedangkan
gigi berjejal pada 2 rahang umumnya terkena
gingivitis sedang. Jumlah gigi berjejal
berpengaruh pada kesehatan gingiva. Semakin
banyak jumlah gigi berjejal maka semakin banyak
akumulasi plak pada permukaan gigi sehingga
memperberat inflamasi gingiva.
Pasien dengan gigi berjejal pada 1 rahang,
umumnya terkena gingivitis ringan pada rahang
atas sedangkan rahang bawah umumnya terkena
gingivitis sedang. Hal ini mungkin berhubungan
dengan muara kelenjar saliva pada rahang bawah.
Lingual rahang bawah terdapat 2 duktus yang
terus mensekresikan saliva yaitu duktus Warthon
dan Bartholin.20
Saliva yang disekresikan mengandung
mineral-mineral anorganik yang kemudian
mengalami kalsifikasi berupa kalkulus. Kalkulus
yang terbentuk pada gigi rahang bawah dapat
memudahkan retensi plak apabila oral hygiene
tidak dilakukan dengan baik.21 Dari hasil uji
korelasi Pearson Chi-Square untuk hubungan
antara jumlah keterlibatan rahang pada gigi
berjejal dengan gingivitis didapat nilai p=0,023
(p<0,05) yang menunjukkan ada hubungan
bermakna antara jumlah keterlibatan rahang pada
gigi berjejal dengan gingivitis.
KESIMPULAN
Dalam hubungan antara gigi berjejal
dengan gingivitis dapat disimpulkan bahwa jenis
kelamin tidak berhubungan dengan gingivitis.
Gingivitis dapat terjadi baik pada pria maupun
wanita dengan gigi berjejal. Faktor usia pada gigi
berjejal berhubungan dengan gingivitis. Gigi
berjejal sama halnya dengan gigi tidak berjejal,
keduanya dapat terjadi gingivitis. Pelaksanaan
teknik oral hygiene yang baik dapat mencegah
terjadinya gingivitis. Terdapat hubungan antara
jumlah keterlibatan rahang pada gigi berjejal
dengan gingivitis. Semakin banyak jumlah gigi
yang berjejal maka semakin banyak akumulasi
plak pada permukaan gigi sehingga memperberat
inflamasi gingiva.
SARAN
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut
dengan jumlah sampel yang lebih besar agar dapat
memberikan hasil yang lebih akurat. Subyek perlu
diberikan edukasi terlebih dahulu dalam
melakukan teknik oral hygiene agar dapat
diperoleh keseragaman dan dapat meningkatkan
keakuratan hasil penelitian. Penelitian selanjutnya
sebaiknya mengklasifikasikan gigi berjejal dalam
kelompok ringan, sedang, dan berat agar dapat
melihat tingkat keparahan gigi berjejal yang
memengaruhi gingivitis.
DAFTAR PUSTAKA
1. Perry DA, Beemsterboer PL. Periodontology
for Dental Hygienist. Ed ke- 3. St.Louis:
Saunders Elsevier; 2007: 66-70, 103-4
2. Reddy S. Essentials of Clinical
Periodontology and Periodontics. Ed ke-2.
New Delhi: Jaypee Brothers Medical
Publishers; 2008: 145-6
3. Laskaris G. Color Atlas of Oral Diseases in
Children and Adolescents. New York:
Thieme; 2000
4. Permana H. Promosi Doktor Yuniarti
Soeroso. 2011. Jakarta: Universitas
Indonesia (cited 2011 Sept 2). Available
from:
http://old.ui.ac.id/id/news/archive/5185
5. Howe RP, McNamara JA, O’Connor KA. An
examination of dental crowding and its
relationship to tooth size and arch. Am J
Orthod.1983; 83:363
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 21 – 27
27
6. Golwalkar SA, Msitry KM. An evaluation of
dental crowding in relation to the mesiodistal
crown widths and arch dimensions. J Ind
Orthod Soc. 2009; 43:22
7. Puscasu C, Totolici D, Dumitriu A, Dumitriu
HT. Laporan Kasus. Oral health and dental
management in Black Sea Country.
Instanbul. 2005
8. Gusmao ES, Queiroz RDC, Coelho RS,
Cimoes R, Santos RL. Association between
malpositioned teeth and periodontal disease.
Dental Press J Orthod 2011;4
9. Schroeder MDS, Ribeiro RLU. Evaluation of
periodontal index of gingival and plaque with
dental crowding in development of gingivitis
in children and adolescents. Revista
Sal.Brasileira de Odontologia 2004
10. Elley BM, Manson JD. Periodontics. Ed ke-
5. London: Wright; 2004: 112,144,191-2
11. Reddy VC, Kumar BRA, dan Ankola A.
Relationship between gingivitis and
anterior teeth irregularities among 18 to 26
years age group: a hospitalbased study in
Belgaum, Karnataka. J Oral Health Comm
Dent. 2010;4:64.
12. Rai B, Kaur J, Kharb S. Pregnancy gingivitis
and periodontitis and its systemic effect. The
Internet Journal of Dental Science 2008;6:2
13. American Academy of Periodontology.
Treatment of plaque-induced gingivitis,
chronic periodontitis, and other clinical
conditions. American Academy of
Periodontology. 2004; 36:14
14. Carranza FA. Glickman's Clinical
Periodontology. Ed ke-10. Philadelphia:
W.B. Saunders Company; 2006: 728 – 45
15. Notohartojo IT, Halim FX. Gambaran
kebersihan mulut, gingivitis pada murid
sekolah dasar di Puskesmas Sepatan,
kabupaten Tangerang. Media Litbang
Kesehatan. 2010; 4:179-186.
16. Zahnmed SM. Subgingival plaque due to
gingivitis and inactive periodontitis sites in
the adult periodontitis patient. 1995. USA:
Pubmed (cited 2011 Sept 2). Available from:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/78784
15
17. Amoian B, Moghadamnia AA, Barzi S,
Sheykholeslami S, Rangiani A. Salvadora
persica extract chewing gum and gingival
health: Improvement of gingival and probe-
bleeding index. Complement Ther Clin
Pract. 2010; 16:121-3
18. Gehrig JS, Willmann DE. Foundations of
Periodontics for the Dental Hygienist. Ed ke-
2. Philadelphia: Lippincott Williams &
Wilkins; 2008:154-5
19. Carranza F A, Newman MG. Carranza’s
Clinical Periodontology. Ed ke-9.
Philadelphia: W. B. Saunders Company;
2004: 269
20. Wiebe CB, Putnins EE. The periodontal
disease classification system of the American
Academy of Periodontology – An update. J
Can Dent Assoc. 2000; 66:594-7
21. Wolf HF, Hassell TM. Color Atlas of Dental
Hygiene. Ed ke-1. New York: Georg Thieme
Verlag; 2006:68-70,80
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 28 – 32
28
Pertumbuhan Linier (stature) dan Tulang Dentofasial pada Penderita Talasemia
Beta Mayor
(Studi Pustaka)
Loes D Sjahruddin
Departemen Pedodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti
ABSTRACT
Background: Thalassemia is an inherited genetic disorder of hemoglobin synthesis. Stunted growth
of bones and growth retardation are found in Thalassemia β mayor patients. Objective: The aim of
this paper was to provide knowledge that the growth of the body can be observed through
anthropometric measurements. Literature review: There are several anthropometric measurements
that are used as indicators of general growth, including weight, height, head circumference
measurement, soft tissue measurements, measurement of chest circumference and growth of dentition.
Normal weight and height have a relationship with a proportional dentofacial bones. Therefore, in a
thalassemia β mayor patient, disharmony of the growth of the dentofacial bones are due to the
deviation of growth in the dentofacial complex, and the short stature of an individual is a growth
deviation due to less optimal linear growth. Conclusion: In Thalassemia β mayor patients, stunted
growth of bones is apparent due to growth retardation.
Keywords : Thalasemia , stature, dentofacial
PENDAHULUAN
Talasemia adalah penyakit kelainan darah
bawaan yang diturunkan secara autosomal
resesif, dengan gejala utama anemia.1 Kelainan
genetik ini disebabkan gangguan pembentukan
rantai globin yang terdapat pada hemoglobin.
Penderita talasemia akan mengalami anemia
hemolitik yang disebabkan oleh kurangnya atau
tidak adanya sintesis rantai globin yang
merupakan penyusun hemoglobin, bisa rantai
alfa atau rantai beta.2 Salah satu akibat dari
penyakit talasemia ini adalah terjadinya
gangguan pertumbuhan dan perkembangan tubuh
penderita. Khususnya pada penderita talasemia
akan terjadi deformitas tulang terutama pada
tulang ceper, seperti pada tulang wajah.
Adanya gangguan pertumbuhan mungkin
merupakan gejala dini dari suatu penyakit. Pada
penderita talasemia, akibat penyimpangan
pertumbuhan akan mengakibatkan
ketidakharmonisan skeletal. Bila terjadi
penyimpangan pertumbuhan pada kompleks
kraniofasial khususnya gigi geligi dan rahang
akan mengakibatkan gangguan pada kesehatan
mulut, fisik, estetik dan mental seseorang.
Umumnya proses tumbuh kembang anak
berjalan bersamaan dan merupakan proses yang
dilalui oleh setiap anak menuju dewasa.. Untuk
memantau pertumbuhan tubuh dapat diamati
melalui pengukuran secara antropometrik.3 Ada
beberapa pengukuran antropometrik yang
dipakai sebagai indikator pertumbuhan umum,
antara lain berat badan, tinggi badan, pengukuran
lingkar kepala, pengukuran jaringan lunak,
pengukuran lingkar dada serta pertumbuhan gigi
geligi.4 Wajah yang serasi merupakan hasil
pertumbuhan tulang fasial yang normal. Ada
dugaan, berat badan dan tinggi badan yang
normal mempunyai hubungan dengan wajah
yang proporsional. Oleh karena itu anomali
tulang dentofasial terjadi akibat deviasi tumbuh
kembang pada kompleks dentofasial, dan
perawakan pendek seorang individu merupakan
penyimpangan tumbuh kembang akibat
pertumbuhan linier yang kurang optimal dengan
tidak lupa membandingkannya dengan pola
pertumbuhan anggota keluarga yang lainnya.
Pertumbuhan Tulang Dentokraniofasial
Kompleks kraniofasial terdiri dari berbagai
komponen tulang yang saling berkaitan.
Kraniofasial terdiri dari basis kranium, tulang
kalvarium, kompleks nasomaksila dan
mandibula.5 Tulang kraniofasial mempunyai pola
pertumbuhan yang kompleks. Pada waktu lahir
kranium terdiri dari 45 buah tulang yang terpisah
satu sama lainnya oleh kartilago atau jaringan
ikat. Setelah dewasa, dengan adanya proses
penyatuan yang sempurna dari beberapa tulang
maka ke 45 buah tulang tersebut menjadi 22
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 28 – 32
29
buah tulang. Setelah proses osifikasi selesai, 14
dari 22 buah tulang membentuk tulang
fasial/viserokranium dan 8 buah tulang
membentuk kranium/ neurokranium.6
Tulang kranium/neurokranium terdiri dari
tulang kalvarium atau tulang tempurung kepala
dan basis kranium atau dasar kepala tempat otak
terletak. Tulang fasial/ viserokranium terdiri dari
kompleks nasomaksila dan mandibula. Pola
pertumbuhan neurokranium yaitu kalvarium dan
basis kranium posterior mengikuti sistem neural,
tetapi pertumbuhan basis kranium anterior
mengikuti pola pertumbuhan neural dan somatik.
Pertumbuhan viserokranium yang terdiri dari
kompleks nasomaksila dan mandibula mengikuti
pola pertumbuhan somatik. Neurokranium
bertumbuh dengan cepat pada periode prenatal
untuk otak yang juga berkembang dengan cepat.
Menjelang usia 2 tahun ukuran kranium
mencapai 87%, usia tujuh tahun telah mencapai
90% volume dewasa dan pada usia 10 tahun
telah mencapai 95% volume dewasa.7
Sebaliknya pertumbuhan tulang fasial lebih
lambat dibandingkan kranium tetapi berlangsung
lebih lama.
Pertumbuhan kompleks nasomaksila atau
wajah bagian atas dipengaruhi oleh pertumbuhan
basis kranial. Pertumbuhan fasial meliputi
pertumbuhan tinggi fasial (arah vertikal),
pertumbuhan lebar fasial (arah transversal), dan
pertumbuhan kedalaman fasial (arah
anteroposterior). Pusat pertumbuhan maksila
terdapat pada sutura-sutura dari kompleks
nasomaksila. Pertumbuhan fasial yang paling
nyata adalah adanya penambahan ukuran tinggi
fasial 3 – 4 kali, pertumbuhan lebar fasial 2 kali
dan pertumbuhan anteroposterior 1.5 kali. Hasil
akhir pertumbuhan maksila mengubah fasial
bawah orang dewasa menjadi relatif lebih tinggi,
lebih lebar dan lebih panjang.
Wajah bagian bawah dibentuk dari sebuah
tulang yang berdiri sendiri yaitu mandibula.
Mandibula pada anak yang baru lahir sangat
kecil, yang berbentuk melengkung hampir lurus
dan terdiri atas dua bagian yang sama besar.
Perkembangan kondilus masih sangat sedikit.
Kedua bagian mandibula ini dipisahkan dibagian
tengah oleh simfisis menti yang terdiri dari
jaringan fibrosa. Kedua rami mandibula ini pada
waktu lahir berbentuk amat pendek dan kondilus
sama sekali belum berkembang.7 Pada akhir
kehidupan pertama, kedua bagian mandibula
yang terpisah itu akan menutup oleh simfisis
yang mengalami perkapuran menjadi tulang.
Pusat pertumbuhan mandibula terjadi pada
prosesus koronoideus, prosesus kondiloideus,
ramus, korpus mandibula dan dagu. Lebar
mandibula mengikuti pertumbuhan kranium
karena tulang kondilus mandibula berhubungan
dengan tulang kranium. Pertumbuhan kompleks
nasomaksila mencapai 80% pada umur 6 tahun
dan tidak banyak mengalami akselerasi
pertumbuhan puber. Jika pertumbuhan tulang
maksila tidak sesuai dengan pertumbuhan
mandibula, maka akan terjadi anomali
dentofasial.8
Gangguan Pertumbuhan Linier pada
Penderita Talasemia Beta
Pertumbuhan linier seorang individu
dipengaruhi oleh faktor intrinsik maupun faktor
ekstrinsik yang saling berkaitan satu sama
lainnya. Nutrisi merupakan faktor lingkungan
yang penting untuk mencapai tumbuh kembang
yang optimal oleh karena nutrisi mutlak
diperlukan oleh setiap mahluk hidup untuk
bertumbuh dan berkembang serta berfungsi
secara maksimal.9
Pertambahan tinggi badan yang paling
pesat terjadi dalam kurun waktu 2 tahun sesudah
kelahiran, kemudian menjadi lambat sampai
kira-kira usia 10 tahun pada anak perempuan dan
kira-kira usia 12 tahun pada anak laki-laki.
Setelah itu laju pertumbuhan dimulai lagi sampai
kira-kira usia 16 tahun pada perempuan dan kira-
kira usia 18 tahun pada laki-laki.10
Gangguan pertumbuhan pada penderita
talasemia dapat berupa berat badan dan
panjang/tinggi badan lebih rendah dari standar
rata-rata, kecepatan pertumbuhan yang kurang,
berkurangnya ketebalan lemak tubuh sampai
berupa gangguan pubertas.11 Tinggi badan
terutama digunakan sebagai indikator untuk
mengamati suatu proses pertumbuhan. Berat
badan lebih erat kaitannya dengan status gizi dan
keseimbangan cairan, namun dapat digunakan
sebagai data tambahan untuk menilai
pertumbuhan. Deviasi pertumbuhan ini selain
oleh karena masukan nutrien yang kurang, juga
karena berbagai faktor seperti hipoksia seluler
dan gangguan endokrin akibat hemolisis dan
anemia kronik.12
Pada penderita talasemia sebagai respons
terhadap hemolis yang terjadi, maka secara
fisiologik akan terjadi peningkatan eritropoiesis.
Eritropoiesis yang terjadi pada sumsum tulang
akan mengakibatkan deformitas pada tulang.
Fusi prematur bagian epifisis tulang-tulang
panjang menyebabkan memendeknya bagian
proksimal tulang humerus. Penyimpangan
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 28 – 32
30
pertumbuhan ini mengakibatkan banyak
penderita talasemia mempunyai perawakan yang
pendek.13,14
Batas antara gizi baik dan gizi kurang
menurut World Health Organization (WHO)
adalah persentil 3 sedangkan batas antara gizi
baik dan gizi lebih adalah persentil 97. Bila
dilihat perbandingan tinggi badan terhadap umur,
maka anak yang berada di bawah garis persentil
3 disebut perawakan pendek, yang berada di atas
garis persentil 97 disebut perawakan tinggi,
sedangkan anak yang berada di antara persentil
97 dan 3 disebut perawakan normal. Dalam
menentukan pertumbuhan normal, laju
pertumbuhan lebih bermanfaat daripada kurva
pertumbuhan standar. Pertumbuhan merupakan
proses aktif, maka dianjurkan melakukan
pengukuran secara berkala. Untuk anak di bawah
satu tahun dianjurkan pemeriksaan berkala setiap
bulan, usia 1 – 5 tahun setiap 3 bulan, dan di atas
5 tahun setiap 6 bulan.15
Gangguan Tumbuh Kembang pada Penderita
Talasemia Beta
Telah diketahui talasemia adalah suatu
penyakit genetik yang disebabkan oleh gangguan
sintesis rantai globin yang menyusun
hemoglobin. Gangguan berupa kekurangan rantai
globin tersebut menimbulkan serangkaian gejala
klinis. Namun pada penderita tertentu gejala
klinis sangat minim atau bahkan tidak ada.
Talasemia beta merupakan bentuk talasemia
yang paling banyak ditemukan. Secara klinis
talasemia beta dibagi menjadi 3 golongan:
talasemia mayor yaitu bentuk homozigot yang
memberikan gejala klinis berat, talasemia
intermedia, dan talasemia minor yang tidak
memperlihatkan gejala klinis.2,16
Pada penderita talasemia terjadi proses
hemolisis sehingga terjadi anemia kronis dan
selanjutnya berakibat terjadinya hipoksia
jaringan. Sebagai respons terhadap hemolisis
yang terjadi, maka secara fisiologik akan terjadi
peningkatan eritropoiesis. Eritropoiesis yang
terjadi pada sumsum tulang akan mengakibatkan
deformitas tulang terutama ceper seperti pada
tulang wajah. Apabila penyakit ini tidak
ditangani dengan baik maka dalam
pertumbuhannya anak akan tampak pucat, tidak
ada nafsu makan, diare, berkurangnya lemak
tubuh dan jaringan otot serta dapat disertai
demam yang berulang akibat infeksi. Hal lain
yang tampak pada penderita talasemia akibat
anemia yang berat dan proses hemolisis adalah
terjadinya gangguan pertumbuhan dan retardasi
perkembangan dan hal ini dikaitkan dengan
kemungkinan adanya perubahan pada kelenjar
hipofise.17 Gangguan pertumbuhan akibat anemia
yang khronis dan kekurangan gizi ini
menyebabkan banyak penderita talasemia
mempunyai perawakan tubuh yang pendek.16
Hemosiderosis pada hati menyebabkan
penurunan produksi somatomedin, yaitu faktor
yang bertanggung jawab terhadap sekresi
hormon pertumbuhan dan menstimulasi
pertumbuhan tulang rawan.16,18 Pengobatan
talasemia pada dasarnya hanya bersifat
simtomatik dan suportif berupa transfusi darah
secara teratur seumur hidup dan pemberian kelasi
besi, karena sampai saat ini belum ada
pengobatan kausal.
Gangguan Pertumbuhan Dentokraniofasial
pada Penderita Talasemia Beta
Pengukuran pada tulang fasial dapat
dilakukan baik secara antropometri, melalui
pengukuran langsung pada kepala dan fasial
subjek maupun dengan bantuan radiografi, yaitu
melalui radiografik sefalometri. Pengukuran
antropometri dan sefalometri dapat menunjukkan
perubahan fasial dalam arah anteroposterior,
vertikal, dan mediolateral.
Penyimpangan pertumbuhan pada
komponen dentofasial dapat diketahui melalui
pengukuran linier dan anguler pada sefalometri,
kemudian membandingkannya dengan norma
ukuran baku subjek normal yang disesuaikan
dengan kelompok ras, umur, dan jenis kelamin.
Kelainan dentofasial tersebut dapat terjadi antara
hubungan maksila dan mandibula terhadap
kranium serta hubungan antara mandibula dan
maksila dalam arah anteroposterior, vertikal, dan
mediolateral.18
Bentuk penyimpangan dalam arah vertikal
dapat berupa gigitan terbuka (open bite) dan
gigitan dalam (deep bite). Untuk menegakkan
diagnosis pada kelainan dentofasial dalam arah
vertikal, proporsi fasial lebih penting daripada
nilai absolut.19
Pembahasan
Kemungkinan diskrepansi yang besar
antara tulang mandibula dan maksila pada
penderita talasemia terjadi akibat mandibula
yang kurang bertumbuh dibandingkan maksila..
Asumsi ini diperkuat dengan hasil penelitian
Pusaksrikit dkk.yang menemukan pada penderita
talasemia laki-laki lebih banyak menderita
maloklusi kelas II dibandingkan penderita
talasemia perempuan. Hal ini mengisyaratkan
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 28 – 32
31
bahwa mandibula pada laki-laki tumbuh lebih
lambat dan mengalami hambatan oleh
pertumbuhan maksila yang luar biasa.14
Demikian pula hasil evaluasi sefalogram
terhadap 32 anak talasemia usia 6 – 18 tahun
dijumpai maloklusi skeletal kelas II sebanyak
90,6% namun tidak terdapat perbedaan jenis
kelamin yang berarti (Retno Hayati, 1993). Pola
dentoskeletal anak talasemia menurut Retno
Hayati (1998) lebih cembung dibandingkan
dengan anak normal sebagai akibat posisi
mandibula yang retrognati dan ukuran korpus
mandibula yang lebih pendek. Tampaknya
bagian kortikal padat dari mandibula menahan
perluasan pertumbuhan tulang mandibula.
Tampaknya bagian kortikal padat dari mandibula
menahan perluasan pertumbuhan tulang
mandibula. Perubahan-perubahan pada tulang itu
dapat terjadi diawal kehidupan dan cenderung
menetap, terutama pada tulang tengkorak.20
Selanjutnya respon terhadap anemia dan
eritropoeisis yang tidak efektif pada penderita
talasemia menyebabkan terjadinya hiperplasia
eritroid yang hebat dalam sumsum tulang dengan
akibat terjadinya deformitas pada tulang,
terutama pada tulang tengkorak, tulang panjang,
kaki dan tangan. 17,21
Hasil penelitian Retno Hayati
menyatakan retardasi pertumbuhan gigi dan
skelet kraniofasial pada subyek talasemia sejalan
dengan retardasi pertumbuhan somatik. Dari
hasil beberapa penelitian yang sudah dilakukan
dapat disimpulkan bahwa ada keterkaitan
penyimpangan pertumbuhan tubuh secara linier
dengan penyimpangan pertumbuhan pada tulang
komponen dentofasial. Perubahan pada tulang
akibat proses perluasan rongga sumsum tulang
akan mengakibatkan penipisan pada bagian
korteks tulang (osteoporosis) sehingga dapat
terjadi fraktur patologis.
KESIMPULAN
Gangguan pertumbuhan yang terjadi pada
seorang penderita talasemia yang tidak diobati
berupa perubahan pada tulang akibat proses
perluasan rongga sumsum tulang. Pemberian
transfusi untuk mengurangi akibat anemia kronik
yang dapat menimbulkan hipoksia pada jaringan
akan mengakibatkan terjadinya kelainan pada
berbagai organ, tulang dan gigi.
Transfusi harus diberikan dengan disertai
kelasi besi untuk mengeluarkan kelebihan besi
dalam tubuh. Jika diagnosis cepat ditegakkan
dan anak mendapat transfusi darah secara teratur,
pertumbuhan selanjutnya menjadi relatif normal.
Gangguan pertumbuhan tulang dentofasial
sejalan dengan pertumbuhan linier (stature) pada
penderita talasemia.
TINJAUAN PUSTAKA
1. Cappellini N, Cohen A, Eleftheriou A, Piga
A, Porter J. Guidelines for the Clinical
Management of Thalassaemia, 2nd
Revised edition. Thalassaemia International
Federation; 2008.
2. Weatherall DJ, Clegg JB. The β thalassemias.
Dalam: Gibbons R, Higgs DR, Old JM,
Oliveri NF, Thein SL, Wood WG,
penyunting. The Thalassemia Syndromes.
Blackwell Science Ltd, London, 2001. h.287-
344.
3. Ismael, S. Tumbuh Kembang Anak dalam
Pencapaian Potensi Sumber Daya
Manusia yang Tangguh. Pidato Pengukuhan
Guru Besar FKUI. Jakarta. 1991.
4. Sularyo, TS. Pertumbuhan Linier (stature)
Anak dan Upaya Pemantauannya dengan
Minat pada Perawakan Pendek/Terlalu
Pendek. Dalam: Rukman Y dkk, Penyunting
Masalah Penyimpangan Pertumbuhan
Somatik pada Anak dan Remaja. Naskah
lengkap PKB IKA FKUI, 16-17 Februari
1993. Hlm: 29-47
5. Proffit WR, Fields HW. Contemporary
Orthodontics. 5rd ed. St. Louis : Mosby Co,
2012. p. 42-55; 165-105.
6. Graber TM. Orthodontics, Principle and
Practice: 3rd ed. Philadelphia: W.B Saunders
Co. 1972. h. 40-75.
7. Ranly, D.M. A Synopsis of Craniofacial
Growth. 2th ed. London: Prentice-Hall
International Inc. 1988. P 82-123.
8. Foster, TD. A Textbook of Orthodontics. 2nd
ed. Blackwell Scientific Publications. 1993. p.
1-25, 75-82.
9. Nasar SS. Aspek Gizi pada Anak dengan
Perawakan Pendek. Dalam : Rukman Y,
Batubara J, Tridjaja B, penyunting. Masalah
Penyimpangan Pertumbuhan Somatic
pada Anak dan Remaja. Naskah lengkap
PKB- IKA XXVIII, FKUI. 1993, 16-17
Februari. Jakarta; Balai Penerbit FKUI; 1993.
p.63-72.
10.Enlow DH. Facial Growth. WB Saunders
Comp. 3th ed. 1990. p. 58-148; 433-34.
11.Fuchs GJ, Tienboon P, Khaled MA, Nimsakul
S, Linpisarn S, Faruque ASG. Nutritional
Support and Growth in Thalassemia Major.
Archives of Disease in Childhood 1997,
76:509-12.
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 28 – 32
32
12.Zakaria P, Gomes MS, Widjaya S. Metode
Baru Skrining Pembawa Gen Thalassemia di
Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan
Kita. Jakarta. Medika 1996; 11:873-.6
13.Davies SC, Cronin E, Gill M et al. Screening
for Sickle Cell Disease and Thalassaemia: a
Systematic Review with Supplementary
Research. Health Technol Assess. 2000;4(3).
14.Drew SJ. & Sachs SA. Management of the
Thalassemia-Induced Skeletal Facial
Deformity. J. Oral Maxillofac Surg. 1997;
55:1331-39.
15.World Health Organization. WHO Child
Growth Standards: Length/Height-for-Age,
Weight-for-Age, Weight-for-Length, Weight-
for-Height, and Body Mass Index-for-Age:
Methods and Development. Geneva,
Switzerland: World Heath Organization.
2006.
16.Wahidiyat I. Penelitian thalasemia di Jakarta.
Disertasi. Jakarta : Universitas Indonesia.
1979.
17.Firkin F, Chesterman C, David P & Rush B.
Clinical Haemotology in Medical Practice. 4th
ed. Blackwell Scientific Publications. 1989;
154-71.
18.Spiliotis BE. β-Thalassemia and Normal
Growth: are They Compatible? Eur J of
endocrinology, 1998, 139:143-4
19.Nanda RS. Growth Pattern in Subjects with
Long and Short Faces. Am J Orthod Dentofac
Orthop 1990; 98:247-58.
20.Retno-Hayati. Pola Deformitas
Dentoskeletal pada Anak Talasemia dan
Faktor Determinannya. Disertasi, Jakarta :
Universitas Indonesia. 1998.
21.Hughes-Jones, NC & Wickramasinghe, SN .
Lecture Notes on Haematology. 8th ed.
Blackwell Scientific Publications Ltd,
Oxford. 2009; 46-51.
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 33 – 40
33
Pentingnya Faktor Ergonomi dalam Penerapan Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Guna Pencegahan Nyeri Punggung Bawah pada Dokter Gigi
(Studi Pustaka)
Mita Juliawati
Staf Pengajar Bagian Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat dan Kedokteran Gigi Pencegahan Gigi Fakultas
Kedokteran Gigi Universitas Trsakti
ABSTRACT
Background: In the competitive era, the implementation of Occupational Safety and Health (OSH)
management, especially in the field of dentistry, is not only for protecting patients, but also for dentists.
Ergonomics is part of Occupational Safety and Health Management. The importance of ergonomic
factors for dentists, among others, is to prevent disorders of the musculoskeletal system that often
occur in the lower back which may causes discomfort. Objective: This literature review aims to raise
awareness of the importance of ergonomic factors in the application of occupational health and safety
management in preventing low back pain in dentists. Conclusion: Ergonomics factors play a role in
preventing lower back pain in dentists. The application of awkward posture correction, ergonomic
equipment design and the application of four-handed dentistry affect the success of occupational health
and safety management systems in the prevention of lower back pain.
Keyword: ergonomics, occupational safety and health, lower back pain, dentist
PENDAHULUAN
Dalam era kompetitif saat ini, penerapan
manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di
setiap bidang usaha yang melibatkan pekerja
merupakan suatu kewajiban, Perlunya manajemen
keselamatan dan kesehatan kerja khususnya
dalam bidang kedokteran gigi tidak hanya untuk
melindungi pasien, tetapi untuk melindungi diri
dokter gigi. Sebagai contoh hal yang sering terjadi
karena kelalaian dokter gigi terhadap manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam hal ini
faktor ergonomi. Pentingnya faktor ergonomi
bagi pasien dan dokter gigi, antara lain guna
mencegah timbulnya gangguan pada sistem
muskulo skeletal. Hal yang sering terjadi adalah
nyeri punggung bawah atau low back pain yang
dapat menyebabkan rasa tidak nyaman pada saat
dokter gigi bekerja.
Data mutakhir menjelaskan bahwa banyak
dokter gigi di dunia yang pernah mengalami nyeri
punggung bawah. Menurut Alexopoulos et al
sekitar 46% dari dokter menemukan 77,1% dokter
gigi mengalami rasa sakit ini. Studi lain di Arab
Saudi disitir oleh Abduljabbar et al bahwa 52,1%
dari dokter gigi di sana pun mengalami kondisi
serupa.1
Salah satu penyebab sindroma
muskuloskeletal pada dokter gigi adalah karena
dokter gigi hanya memperhatikan kenyamanan
bagi pasien yang dirawat, tetapi kurang
memperhatikan kenyamanan bagi diri mereka
sendiri saat merawat pasiennya. Dokter gigi
menganggap bahwa mereka yang harus bergerak
menghampiri pasien, dari pada mengatur posisi
duduk pasien di atas dental chair. Meskipun
bekerja dengan postur netral dapat mencegah atau
mengurangi sindroma muskuloskeletal,
kebanyakan dokter gigi tidak menyadari
pentingnya manfaat sistem ergonomi dengan
posisi yang baik saat merawat pasien. Postur yang
baik dan benar membutuhkan peralatan yang baik
juga, misalnya bentuk kursi operator yang
ergonomi dapat mendukung tulang punggung
pada posisi yang baik.3 Pencapaian keselamatan
dan kesehatan kerja tidak lepas dari peran
ergonomi, karena ergonomi berkaitan dengan
posisi orang yang bekerja, khususnya dalam
rangka efektivitas dan efisiensi kerja.
Dari telaah kasus diatas, masalah faktor
ergonomi pada praktik dokter gigi perlu dibahas
bagaimana pentingnya faktor ergonomi dalam
penerapan manajemen K3 untuk menghindari
risiko terjadinya kecelakaan kerja khususnya di
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 33 – 40
34
bidang kedokteran gigi yaitu nyeri punggung
bawah yang kerap menyerang dokter gigi.
TINJAUAN PUSTAKA
Ergonomi
Sejarah dan Pengertian Ergonomi
Pada tanggal 16 Februari 1950 terminologi
ergonomi diadopsi dan ergonomi menjadi suatu
disiplin ilmu.4 Menurut Syamsyul ma’arif dan
Hendri Tanjung ergonomi adalah studi tentang
bagaimana manusia secara fisik berinteraksi
dengan alat-alat yang digunakannya sehingga
didapatkan kondisi dimana pekerjaan menjadi
sehat, aman dan nyaman. 5
Ruang Lingkup dan Tujuan Ergonomi
Ruang lingkup ergonomi berhubungan
dengan karakter psikologi seseorang yang
mempengaruhi disain dan kegunaan dari tempat
dan, posisi bekerja, dan atau suatu pengoperasian
untuk memastikan apakah disain tersebut
berhubungan dengan tugas, peralatan,
perlengkapan serta prosedur yang sesuai dengan
keterbatasan manusia dan kapasitas
penggunaannya. Intinya sebagai studi tentang
aspek-aspek manusia dalam lingkungan kerjanya
yang ditinjau secara anatomi, fisiologi, psikologi,
engineering, manajemen dan disain.6
Tujuan-tujuan dari penerapan ergonomi
adalah sebagai berikut:
a. Meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental
melalui upaya pencegahan cidera dan penyakit
akibat kerja, menurunkan beban kerja fisik dan
mental, mengupayakan promosi dan kepuasan
kerja.
b. Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui
peningkatan kualitas kontak sosial dan
mengkoordinasi kerja secara tepat, guna
meningkatkan jaminan sosial baik selama
kurun waktu usia produktif maupun setelah
tidak produktif.
c. Menciptakan keseimbangan rasional antara
aspek teknis, ekonomis, dan antropologis dari
setiap sistem kerja yang dilakukan sehingga
tercipta kualitas kerja dan kualitas hidup yang
tinggi.7
Guna mencapai tujuan-tujuan tersebut
perlu penerapan ergonomis yang tepat untuk
mencegah cedera yang dapat berkembang serta
menyebabkan cacat jangka panjang. Dalam
bekerja penerapan Ergonomi yang perlu
diperhatikan adalah:
a. Posisi Kerja, Terdiri dari posisi berdiri serta
duduk, posisi berdiri dimana posisi tulang
belakang vertikal dan berat badan tertumpu
secara seimbang pada dua kaki, sedang posisi
duduk adalah saat kaki tidak terbebani dengan
berat tubuh dan posisi stabil selama bekerja.
b. Proses Kerja, Para pekerja dapat menjangkau
peralatan kerja sesuai dengan posisi waktu
bekerja serta sesuai dengan ukuran
anthropometrinya.
c. Tata Letak Tempat Kerja, Tata letak
merupakan rencana fasilitas, menganalisa,
membentuk konsep, dan mewujudkan sistem
pembuatan barang atau jasa.
d. Mengangkat Beban, Berbagai cara dalam
mengangkat beban yaitu, dengan bahu, tangan,
kepala atau punggung. Beban yang terlalu
berat dapat menimbulkan cedera tulang
punggung, jaringan otot dan persendian akibat
gerakan yang berlebihan.8
Setiap pekerjaan mempunyai sistem, dan pada
ergonomi dikenal sistem kerja yang terdiri dari:
Manusia sebagai pekerja, Pekerjaan yang akan
dikerjakan, Peralatan yang digunakan dan
lingkungan kerja dimana pekerja bekerja.9 Dalam
bidang kedokteran gigi ergonomi mencakup
banyak konsep seperti, bagaimana dokter gigi
memposisikan diri pada pasien, menggunakan
peralatan, disain tempat atau lingkungan kerjanya
dan bagaimana semua ini berdampak pada
kesehatan dokter gigi.
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
Kerja
Pengertian Manajemen
Manajemen berasal dari kata “to manage”
yang berarti mengatur. Hasibuan berpendapat
manajemen adalah ilmu seni mengatur proses
pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-
sumber lainnya secara efisien dan efektif untuk
mencapai tujuan. 10 Arti lain adalah suatu proses
untuk mencapai suatu tujuan tertentu.11
Manajemen identik dengan pengelolaan,
pembinaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, dan
ketatapengurusan, walau sebenarnya memeiliki
konsep lebih luas dari daripada hal tersebut.12
Fungsi Manajemen
Fungsi manajemen menurut Fayol di awal
abad ke-20 adalah elemen-elemen dasar yang
akan selalu ada dan melekat di dalam proses
manajemen yang akan dijadikan acuan oleh
seorang manajer dalam melaksanakan kegiatan
untuk mencapai suatu tujuan. Empat fungsi
manajemen terdiri dari:
1. Perencanaan (Planning),
2. Pengorganisasian (Organizing),
3. Pengarahan (Comanding/Actuating)
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 33 – 40
35
4. Pengendalian Controlling)13
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
merupakan hal yang penting, karena dampak
kecelakaan dan penyakit kerja tidak hanya
merugikan lingkungan kerja tetapi juga
merugikan diri para pekerja sendiri.
Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3)
Menurut OSHA (2003), Keselamatan dan
Kesehatan kerja (K3) adalah merupakan
multidisiplin ilmu yang terfokus pada penerapan
prinsip ilmiah dalam memahami adanya risiko
yang mempengaruhi keselamatan dan kesehatan
kerja manusia dalam lingkungan industri ataupun
lingkungan di luar industri, serta merupakan
profesionalisme dari berbagai disiplin ilmu yaitu
fisika, kimia, biologi dan ilmu perilaku yang
diaplikasikan dalam manufaktur, transportasi,
penyimpanan dan penanganan bahan
berbahaya. 14
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi K3
Faktor-faktor yang mempengaruhi
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) antara
lain adalah beban kerja, kapasitas kerja dan
lingkungan kerja.15
Beberapa contoh penyakit akibat kerja
(PAK) antara lain: silicosis (karena paparan debu
silica), asbestosis (karena paparan debu asbes),
low back pain (karena pengangkutan manual),
white finger syndrom (karena getaran mekanis
pada alat kerja).16,
Penyakit akibat kerja pada dokter gigi
umumnya berkaitan dengan faktor fisik, kimia,
biologis, ergonomi dan psikologis.
a. Faktor Fisik
Meliputi kebisingan, getaran akibat mesin
dapat menyebabkan stress dan ketulian,
pencahayaan yang kurang di ruang kamar
pemeriksaan, laboratorium, ruang perawatan
dan kantor administrasi dapat menyebabkan
gangguan penglihatan dan kecelakaan kerja,
suhu dan kelembaban yang tinggi di tempat
kerja, terimbas kecelakaan/kebakaran akibat
lingkungan sekitar, terpapar radiasi.
b. Faktor Kimia
Berbagai bentuk bahan kimia dapat
memberikan pengaruh terhadap tubuh yaitu:
debu (dust), cairan (liquid), asap (fumes,
smokes), gas (gasses), uap (vapours), bahan
pelarut.
c. Faktor Biologis
Lingkungan kerja terutama pada Pelayanan
Kesehatan, sangat disukai bagi berkembang
biaknya strain kuman yang resisten, terutama
kuman-kuman seperti E. colli, Lactobacilli,
staphylococci, dan pyogenic yang bersumber
dari pasien, benda-benda yang terkontaminasi
dan udara. Virus yang menyebar melalui
kontak dengan darah dan cairan tubuh
(misalnya HIV dan Hepatitis B) dapat
menginfeksi pekerja hanya akibat kecelakaan
kecil dipekerjaan, misalnya karena tergores
atau tertusuk jarum yang terkontaminasi virus.
d. Faktor Ergonomi
Sebagai ilmu, teknologi dan seni berupaya
menyesuaikan alat, cara, proses dan
lingkungan kerja terhadap kemampuan
manusia untuk terwujudnya kondisi dan
lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman
dan tercapai efisiensi yang setinggi-tingginya.
Posisi kerja yang salah dan dipaksakan dapat
menyebabkan mudah lelah sehingga kerja
menjadi kurang efisien dan dalam jangka
panjang dapat menyebakan gangguan fisik dan
psikologis (stress) dengan keluhan yang paling
sering adalah nyeri punggung bawah (low back
pain).
e. Faktor Psikologis, Beberapa contoh faktor
psikososial di tempat kerja terutama dalam
bidang kesehatan yang dapat menyebabkan
stress:
1. Pelayanan kesehatan sering kali bersifat
emergency dimana pekerja dalam bidang
kesehatan di tuntut untuk memberikan
pelayanan yang tepat, cepat disertai dengan
kewibawaan dan keramahan-tamahan;
2. Pekerjaan pada unit-unit tertentu yang
sangat monoton;
3. Hubungan kerja yang kurang serasi antara
pimpinan dan bawahan atau sesama teman
kerja;
4. Beban mental karena menjadi panutan bagi
mitra kerja di sektor formal ataupun
informal. 16
Hubungan Faktor Ergonomi dengan Nyeri
Punggung Bawah pada Dokter Gigi
Dokter gigi perlu mempelajari dan
memahami ergonomi karena dengan paham
ergonomi akan mempermudah evaluasi setiap
pekerjaan, meskipun ilmu pengetahuan dalam
ergonomi terus mengalami kemajuan dan
teknologi yang digunakan dalam pekerjaan
tersebut terus berubah.
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 33 – 40
36
Penatalaksanaan dan metode pekerjaan
dokter gigi dapat dievaluasi dari aspek ergonomi
khususnya tentang gangguan muskuloskeletal
yang menunjukkan bahwa dokter gigi bekerja
dalam kondisi rentan terkena gejala tersebut.
Kelainan yang sering dijumpai adalah nyeri
punggung bawah (low back pain), keluhan pada
leher, pundak dan lengan atas.17Dokter gigi dalam
menjalankan profesinya akan menghabiskan
waktu yang lama dengan posisi statis, karena
berhubungan dengan pekerjaannya yang
melakukan pemeriksaan dan perawatan gigi dan
mulut pasien, dimana di dalam melakukan
pemeriksaan dan perawatan gigi dan mulut pada
umumnya dokter gigi mempunyai posisi
punggung, tangan dan bahu yang tetap stabil
dalam waktu yang cukup lama.18
Kebanyakan gangguan muskuloskeletal
terjadi karena dokter gigi secara tanpa sadar
berada pada posisi tubuh yang kurang ergonomis
saat merawat pasien, misal preparasi atau
mencabut gigi, postur dokter gigi membungkuk
ke arah pasien, bergerak secara mendadak,
memutar tubuh dari satu sisi ke sisi yang lain.
Seluruh gerakan tersebut dilakukan berkali-kali
dalam jangka waktu yang panjang. Pada kasus
gangguan muskuloskeletal karena faktor
ergonomi, keluhan umum yang dijumpai adalah
keluhan nyeri punggung bawah., diikuti oleh nyeri
pada leher dan bahu.19 Ergonomi dilakukan
sebagai salah satu upaya pencegahan gangguan
nyeri punggung bawah. Faktor-faktor resiko
ergonomi yang dapat menyebabkan nyeri
punggung bawah antara lain:
a. Postur Tubuh Janggal
Faktor Resiko paling sering. Berpotensi
menimbulkan MSDs terutama nyeri punggung
bawah bila dilakukan lebih dari dua jam per
hari dan bekerja dengan leher atau punggung
membungkuk > 30 derajat tanpa tahanan atau
kemampuan mengubah postur.
Gambar 1. Contoh postur tubuh pada saat duduk.
b. Faktor Frekuensi
Frekuensi tinggi dapat menimbulkan kelelahan
dan ketegangan pada otot dan tendon, dapat
berakibat terjadinya radang sendi dan tendon.
Radang ini meningkatkan tekanan pada syaraf.
c. Faktor lama waktu bekerja
Durasi kerja yaitu lama waktu bekerja yang
dihabiskan pekerja dengan postur janggal.
Melakukan pekerjaan tanpa istirahat.
d. Postur Statis
Postur kerja fisik dalam posisi yang sama dan
pergerakan yang sangat minimal, akan
menimbulkan peningkatan beban otot dan
tendon, menyebabkan aliran darah pada otot
terhalang dan menimbulkan kelelahan, rasa
kebas dan nyeri.20.
Nyeri Punggung bawah
Nyeri punggung bawah (Low back pain)
menjadi masalah kesehatan tetapi sering dianggap
sepele, merupakan masalah pada negara-negara
maju dan berkembang. 21 Sekitar 80-90% pasien
nyeri punggung bawah menyatakan bahwa
mereka tidak melakukan usaha apapun untuk
mengobati penyakitnya. Di Amerika Serikat nyeri
punggung bawah menempati urutan kedua
keluhan tersering setelah nyeri kepala.22
Di Indonesia, hasil penelitian pada tahun
2002 ditemukan prevalensi penderita nyeri
punggung bawah sebanyak 15,6%. Angka ini
berada pada urutan kedua tertinggi sesudah
sefalgia dan migren yang mencapai 34,8%. Hasil
penelitian secara nasional yang dilakukan di 14
kota di Indonesia yang juga dilakukan oleh
kelompok studi Nyeri PERDOSSI tahun 2002
ditemukan 18,13% penderita NPB dengan rata-
rata nilai VAS sebesar 5,46±2,56 yang berarti
nyeri sedang sampai berat. 22
Pengobatan pasien dengan Nyeri punggung
bawah adalah fisioterapi, chiropractic
manipulation, terapi pijat, akupunktur dan
berbagai bentuk operasi tulang belakang. 23
Pengertian Nyeri punggung bawah
Gangguan musculoskeletal dengan keluhan
penderita nyeri pada daerah punggung antara
sudut bawah kosta (tulang rusuk) hingga
lumbosacral (sekitar tulang ekor) pada umumnya
karena berbagai macam penyakit dan aktivitas
tubuh yang kurang baik. 24
Klasifikasi Nyeri Punggung Bawah
Menurut International Association for the Study
of Pain (IASP), yang termasuk dalam Nyeri
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 33 – 40
37
Punggung Bawah low back pain terdiri dari:
a. Lumbar Spinal Pain
Nyeri di daerah yang di batasi: superior oleh
garis transversal imajiner yang melalui ujung
prosesus spinosus dari vertebra thorakal
terakhir, inferior oleh garis transversal
imajiner yang melalui ujung prosesus spinosus
dari vertebra sakralis pertama dan lateral oleh
garis vertical tangensial terhadap batas lateral
spina lumbalis.
b. Sacral Spinal Pain
Nyeri di daerah yang dibatasi superior oleh
garis transversal imajiner yang melalui ujung
prosesus sinosis vertebra sakralis pertama,
inferior oleh garis transversal majiner yang
melalui sendi sakrokoksigeal posterior dan
lateral oleh garis imajiner melalui spina iliaka
superior posterior dan inferior.
c. Lumbosacral Pain
Nyeri didaerah 1/3 bawah daerah lumbar
spinal pain dan 1/3 atas daerah sacral spinal
pain.24
Gambar 3. Spine anatomy.
Gejala Nyeri Punggung Bawah
Gejala utama pada nyeri punggung bawah
adalah rasa nyeri. Nyeri terjadi setelah melakukan
aktivitas, gerakan tiba-tiba atau setelah
mengangkat benda atau beban yang berat.25 Nyeri
biasanya diibaratkan dengan kerusakan jaringan,
akan tetapi dapat juga timbul tanpa luka dimana
nyeri timbul tanpa berhubungan dengan sumber
yang dapat diidentifikasi. 26
Data Kasus Nyeri Punggung Bawah pada
Dokter Gigi
Posisi duduk yang salah serta tidak
ergonomis yang dilakukan selama berjam-jam
dan terus menerus menempatkan dokter gigi
sebagai profesi yang sangat rentan untuk
mengalami nyeri punggung bawah, karena saat
praktek dan merawat pasien dokter gigi harus
duduk atau berdiri membungkuk dalam jangka
waktu lama. Terlebih jika jumlah pasien per hari
cukup banyak. 27
Penelitian terhadap nyeri leher & punggung
bawah pada dokter gigi dengan menggunakan
penyebaran kuesioner hasilnya prevalensi nyeri
punggung bawah yang didapatkan dari partisipan
adalah 63%. 28
Studi pada dokter gigi bersuku Flandria
yang tinggal di Belgia didapatkan hasil prevalensi
sebanyak 54% dokter gigi bersuku Flandria
mengalami nyeri punggung bawah.29
PEMBAHASAN
Dokter gigi wajib profesional saat melayani
pasien dalam berbagai kondisi, saat fokus kepada
pasien maka dokter gigi tidak dapat melalaikan
manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja
(K3) untuk dirinya sendiri. Dampak fisik dari
kelalaian manajemen (K3) yang kerap menyerang
dokter gigi adalah gangguan muskuloskeletal
terutama nyeri punggung bawah. Kondisi itu
menimbulkan nyeri yang bila tidak diatasi dapat
mengganggu aktivitas yang akan berdampak pada
penurunan produktivitas dan kualitas kerja.
Penerapan sistem manajemen K3 dalam
pencegahan nyeri punggung bawah yang dapat
dilakukan dokter gigi adalah perbaikan ergonomi
dengan cara koreksi postur janggal pada saat
mengerjakan pasien, pemilihan desain peralatan
yang ergonomis serta menerapkan konsep four-
handed dentistry. Dengan penerapan sistem
manajemen K3 seperti apa yang telah disebutkan
diatas akan didapatkan pergerakan tubuh yang
baik dan diharapkan dapat mengurangi resiko
nyeri pada punggung bawah dan meningkatkan
produktivitas kerja.
Koreksi Postur Janggal
Duduk statis dalam waktu lama adalah hal
yang sering dilakukan dokter gigi ketika bekerja.
Demi kenyamanan pasien dokter gigi tidak sadar
bahwa posisi duduk yang ia lakukan kurang
ergonomis. Terlalu lama duduk dengan posisi
salah akan menyebabkan ketegangan otot-otot
dan ligamentum tulang belakang yang membuat
tekanan abnormal dari jaringan sehingga
menyebabkan rasa sakit.
Penerapan sikap duduk yang baik dan benar
bagi Dokter gigi sehingga dapat meminimalisir
postur janggal pada saat mengerjakan pasien
dengan mencegah agar postur tubuh tidak tegang;
terlalu miring kesamping, memuntir tulang
punggung, membengkok ke depan/membungkuk
menuju posisi tubuh yang baik. Disarankan
beberapa hal seperti, yaitu: Tubuh bagian atas
tegak simetris, punggung dipertahankan tegak dan
tulang panggul (pelvis) sedikit dimiringkan ke
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 33 – 40
38
depan (tidak lebih dari 20 derajat); Kepala
condong ke depan terhadap tubuh tidak lebih dari
20 – 25 derajat; Lengan atas bebas tergantung
pada tubuh dan tidak lebih dari 10 derajat ke
depan; Lengan bawah (forearm) sedikit terangkat
tidak lebih dari 25 derajat; Sudut antara tungkai
atas dan bawah adalah 105 – 110 derajat atau
lebih, sehingga terdapat lebih banyak ruangan
antara tungkai atas dan lengan bawah untuk
menempatkan sandaran kursi dan kepala pasien di
antara ruangan ini; Tungkai atas kiri dan kanan
membentuk sudut tidak lebih dari 45 derajat untuk
mencegah posisi sendi pinggul (hip joint) dalam
keadaan terkunci; Telapak kaki sejajar terhadap
lantai atau agak ke belakang dan segaris dengan
tungkai atas; bila menggunakan pandangan. 17
Gambar 4. Posisi duduk ergonomis dalam
mengerjakan pasien.5
Desain Peralatan Ergonomis
a. Operating stool adalah kursi yang digunakan
oleh dokter gigi. Untuk pemilihan operating
stool yang baik pilih bentuk tempat duduk
yang dapat membantu tubuh dalam posisi yang
benar dengan spinal yang tegak dan dekat
dengan kursi gigi. Bentuk sandaran yang
mendukung punggung dapat menjaga otot
punggung bagian bawah agar tetap tegak dan
lengkungannya dipertahankan. Selain itu, pilih
kursi yang memiliki sandaran lengan karena
sandaran lengan dirancang untuk mengurangi
tekanan dan kelelahan pada otot-otot
punggung bagian atas, leher dan bahu dengan
membentuk sudut tegak lurus terhadap siku
lengan dokter gigi.
b. Dental Loupe adalah alat bantu lihat yang
dapat memperbesar obyek yang dilihat
sehingga memungkinkan dokter gigi dapat
duduk lebih nyaman dengan postur bahu dan
leher yang optimal. Pembesaran minimal dua
kali sudah cukup menghasilkan jarak
pengelihatan yang baik dengan posisi pasien.
Pembesaran yang lebih tinggi ditambah
dengan sistem pencahayaan yang baik dapat
meningkatkan efisiensi penglihatan yang lebih
rinci dan tidak ada hambatan bayangan pada
daerah operasi.
c. Dental Light ialah lampu sorot yang terdapat
pada kursi praktik dokter gigi. Dental light
yang dianjurkan adalah yang tidak terlalu
besar dan lebar, pilih yang sempit, hanya
terfokus pada mulut pasien dan tidak
menghasilkan bayangan yang mengganggu.
Lebih dianjurkan menggunakan dental light
dengan sensor, atau monitor untuk lampu
ditempatkan pada lokasi yang mudah dicapai
tanpa harus memegang tangkai lampu. Pada
dental unit yang dirancang dengan sistem
ergonomi, tombol untuk menyalakan dan
memadamkan dental light sudah menyatu pada
meja kursi dental dan pada assistant console,
sehingga lebih mudah dijangkau dan operator
tidak perlu lagi menyentuh tombol dental light
untuk mengatur posisinya.3
Penerapan Four-Handed Dentistry
Four-handed dentistry merupakan teknik
yang digunakan dalam kedokteran gigi dimana
dokter gigi dan perawat gigi secara bersama
melakukan tindakan perawatan kepada pasien.
Tujuannya adalah untuk mempercepat proses
pekerjaan dan mengurangi kelelahan untuk tenaga
medis gigi serta pasien, memperpendek waktu
perawatan gigi yang diberikan kepada pasien dan
meningkatkan kualitas pekerjaan. Konsep four-
handed dentistry diharapkan dapat mencegah
terjadinya pergerakan yang menegangkan otot.
Agar penerapan konsep four handed dentistry
berjalan dengan baik, dibutuhkan kerja sama yang
baik antara dokter gigi dan asisten dokter gigi.
Masing-masing operator harus saling
bertanggung jawab dan menyadari kebutuhan satu
sama lain.
Prinsip dalam four-handed dentistry
adalah:
a. Dokter gigi diharapkan melatih asisten
sehingga tidak perlu melakukan pergerakan
yang tidak efisien. Misalnya mengambil tang
atau alat pencabutan gigi di daerah yang jauh
dari jangkauannya.
b. Asisten yang membantu dokter gigi harus
mempunyai pengetahuan dan keterampilan
dalam menangani peralatan. Terlatih untuk
mengikuti setiap prosedur perawatan yang
dilakukan dokter gigi.
c. Asisten harus lebih sering menangani
peralatan misalnya saliva ejector, suction
pump, handpiece dan bor, sehingga dokter gigi
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 33 – 40
39
tidak perlu melakukannya sendiri. Idealnya
penanganan peralatan yang dilakukan asisten
adalah 80 – 90% dari waktu kerja, sehingga
dokter gigi hanya berkonsentrasi pada
perawatan pasien.
d. Letak peralatan yang harus ditangani asisten
lebih banyak berada pada sisi asisten untuk
memudahkan pemindahan alat ke dokter gigi.
Posisi alat harus berada di depan asisten dan
jangan di samping asisten, agar tidak perlu
melakukan pergerakan tubuh memutar.
e. Asisten juga harus berada di daerah yang bebas
agar mudah memindahkan alat. Alat yang
dipindahkan sebaiknya melewati batas dagu
pasien. Bidang perawatan (operatory-field)
dibentuk sedemikian rupa sehingga terdapat
ruang bebas, baik bagi asisten, dokter gigi dan
pasien. Kondisi seperti ini menyebabkan
pasien tidak merasa terkurung oleh dokter gigi
maupun asisten. Biasanya ruangan dalam four-
handed dentistry dibagi atas empat daerah
aktivitas (zona) berdasarkan arah jarum jam,
yaitu daerah operator pada posisi arah jarum
jam 7-12, daerah asisten berada pada posisi
arah jarum jam 2-4, daerah statis (untuk
instrument dan bahan) berada pada posisi arah
jarum jam 12-1, dan daerah transfer berada
pada posisi arah jarum jam 4-7.3
Gambar 5. Zona kerja four-handed dentistry
berdasarkan arah jarum jam.
KESIMPULAN
Dari uraian masalah, telaah pustaka dan
pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa
sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan
kerja berperan dalam pencegahan nyeri punggung
bawah pada dokter gigi. Guna menunjang peran
tersebut, maka perlu diperhatikan tatalaksana
dalam hal perencanaan, pelaksanaan serta
evaluasi.
Adapun hal-hal yang dapat mempengaruhi
keberhasilan sistem manajemen keselamatan dan
kesehatan kerja dalam pencegahan nyeri
punggung bawah adalah dengan menerapkan:
Koreksi postur janggal, desain peralatan
ergonomis dan penerapan four-handed dentistry.
DAFTAR PUSTAKA
1. Tommy D.P dan Muhammad Ilyas. Low
Back Pain in Dentists of Indonesia [Online
Article]. 2012. [cited: 25 Juli 2014].
Available:
http://www.podj.com.pk/Dec_2012/p-22.pdf
2. Furlong A. Ergonomic and Dentistry. ADA
News 2000; 31(18): 16-9.
3. Andayasari L, Anorital. Gangguan
Musculoskeletal pada Praktik Dokter Gigi
dan Upaya Pencegahannya [Media Litbang
Kesehatan]. 2012. [cited 19 Juli 2014].
Available:
http://ejournal.litbang.depkes.go.id/index.ph
p/MPK/article/view/2629/612
4. Oborne, David J. Ergonomic at Work:
Human Factors in Design and Development.
England: John Wiley and Sons Ltd; 1995: 5-
8
5. Ma’arif, syamsyul dan Tanjung, Hendri.
Manajemen Operasi. Jakarta: PT. Grasindo.
2003: 393
6. Nurmianto, Eko. Ergonomi, Konsep Dasar
dan Aplikasinya. Ed. Ke-2. Jakarta:
Gunawidya; 2008: 1-30
7. Tarwaka, Solichul H.B, Lilik S. Ergonomi
untuk Keselamatan Kerja dan Produktivitas.
Surakarta: Uniba Press; 2004: 1-20
8. Pusat Kesehatan Kerja Departemen
Kesehatan RI. Ergonomi. [cited: 16 Juli
2014]. Available:
http://www.depkes.go.id/downloads/Ergono
mi.PDF
9. Sarkar PA dan Shigli AL. Ergonomics in
General Dental Practice. People’s journal of
Scientific Research 2012; 5:56-60.
10. Hasibuan, Malayu, S.P. Manajemen Dasar,
Pengertian dan Masalah. Jakarta: PT Toko
Gunung Agung; 2003: 1-5
11. Herujito, Yayat M. Dasar-dasar
Manajemen. Jakarta: PT. Grasindo; 2001: 1-
2
12. Sastrohadiwiryo, B.S. Manajemen Tenaga
Kerja Indonesia Pendekatan Administratif
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 33 – 40
40
dan Operasional. Jakarta: PT. Bumi Aksara;
2005: 1-20
13. Harahap SS. Sistem Pengawasan Manajemen
(Mangement Control System). Jakarta:
Quantum; 2001: 4-5
14. OSHA Standard. (2003). Accident
investigation guide
15. Efendi, Ferry dan Makhfudli. Keperawatan
Kesehatan Komunitas: Teori dan Praktik
dalam Keperawatan. Jakarta: Penerbit
Salemba Medika; 2009: 232-233
16. Tresnaningsih E. Kesehatan dan
Keselamatan Kerja di Laboratorium
[Departemen Kesehatan RI] 2010 [cited 18
Juli 2014]. Available:
http://www.depkes.go.id/downloads/Keseha
tan%20Kerja%20di%20Labkes.PDF
17. Ma’aruf MT. Perubahan Sikap Kerja Dokter
Gigi. Interdental Jurnal Kedokteran Gigi
2007; 5(1): 37-42
18. Wijaya AT, Darwita RR, Bahar A. The
Relation between Risk Factors and
Musculoskeletal Impairment in Dental
Students: a Preliminary Study. Journal of
Dentistry Indonesia. 2011; 18(2):33-37.
19. Shrestha BP, Singh GK, Niraula SR. Work
Related Complaints among Dentists. J Nepal
Med Assoc 2008; 47(170):77-81.
20. Kurniawidjaja, Meily. Teori dan Aplikasi
Kesehatan Kerja. Ed. Ke-1. Jakarta:
Universitas Indonesia; 2010: 1-20, 106-108
21. Hoy D, Brooks P, Blyth F, Buchbinder R.
The Epidemiology of low back pain. Best
Practice & research clinical rheumatology
2010; 24:769-781.
22. Purba JS, Ng DS. Nyeri punggung bawah:
patofisiologi, terapi farmakologi dan non-
farmakologi akupunktur. Medicinus 2008;
21(2): 38-42.
23. Brendan D. Lewis. Lower Back pain.
Canadian journal of CME. 2001.
http://www.stacommunications.com/journal
s/cme/images/cmepdf/april01/lowerbackpai
n.pdf
24. Yuliana. Low Back Pain. CDK 2011; 38 (4):
270-273
25. Healthwise staff. Low Back Pain [Medical
Website]. 2013. [cited 19 Juli 2014].
Available:
http://www.cigna.com/healthwellness/hw/m
edical-topics/low-back-pain-hw56429
26. Dedi Ardinata. Multidimensional nyeri.
Jurnal keperawatan rufaidah Sumatera utara
2007; 2(2):77-81
27. Chowanadisai S, Kukiattrakoon B, Yapong
B, Kedjarune U, Leggat PA. Occupational
Health Problems of Dentists in Southern
Thailand. Int Dent J 2000;50(1):36-40.
28. Duygu Geler Külcü, Gülçin Gülşen, Tuba
Çiğdem Altunok, Davut Küçükoğlu, Sait
Naderi. Neck and Low Back Pain Among
Dentistry Staff. Turkish Jurnal of
Rheumatology 2010; 25:122-129. 29. Peter Leggat, Ureporn Kedjarune and Derek
R. Smith. Occupational Health Problems in
Modern Dentistry: Review. Industrial Health
2007; 45: 611-621
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 41 – 45
41
Perawatan Ortodonti Paska Bedah Ortognati
(Tinjauan Pustaka)
Olivia Piona Sahelangi
Staf Pengajar Bagian Ortodonti Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trsakti
ABSTRACT
Background: In two decades, surgical orthodontics to correct severe malocclusion and skeletal
deformities have been done. Corrective jaw surgery also called orthognathic surgery is performed by
an oral and maxillofacial surgeon to correct a wide range of major skeletal irregularities, including
misalignment of jaws and teeth. Objective: Skeletal dentofacial deformities are associated with
numerous problems including esthetic, functional, and mastication. Collaboration between the
orthodontist and the surgeon is critical. The ability of an orthodontist and a surgeon to coordinate
during treatment is what will lead to a successful outcome. Although much has changed in the field of
orthognathic surgery, the role of an orthodontist in postsurgical orthognathic surgery is critical.
Literature review: Following a recovery period, orthodontic treatment post-surgical orthognathic
surgery is to settle the teeth in good occlusion and alignment and correct any possible skeletal relapse
following surgery. Orthodontic treatment is needed to make adjustments and ensure the stability of the
realigned bite. Examination of the face including evaluation of facial and dental photographs,
cephalometric radiographs should be done postsurgical orthognathic surgery. Conclusion: Achieving
successful treatment outcomes requires implementing an effective treatment plan.
Keyword: orthognathic surgery, skeletal dental deformities, postsurgical orthodontics
PENDAHULUAN
Selama dua dekade terakhir, intervensi
bedah ortognatik dalam merawat deformitas
skeletal telah banyak dilakukan. Kombinasi
perawatan ortodonti dan bedah memberikan hasil
yang lebih baik dalam merawat pasien dengan
skeletal dan dental displasia.1
Terdapat dua puluh persen dari populasi
pasien dengan deformitas dentofasial. Banyak
pasien dengan deformasitas dentofasial dapat
memperoleh manfaat dari perawatan korektif
ortognatik. Perawatan disharmoni rahang maupun
fasial sebaiknya ada kerjasama antara ortodontis
dan ahli beda rahang secara komprehensif.1,2
Potensi relaps setelah bedah ortognati
menjadi bahasan penting dimana perlu
diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi
stabilitas skeletal paska bedah ortognati. Tipe
fiksasi dan besarnya pergerakan yang dilakukan
dalam operasi bedah turut mempengaruhi
kestabilan bedah ortognatik. Selain itu,
keberhasilan koreksi bedah tergantung dari
stabilitas serta respon skeletal dan dental setelah
perawatan bedah ortognatik.2
Paska bedah ortognatik, penting bagi
ortodontis melakukan evaluasi, observasi dan
melanjutkan perawatan akhir. Adanya
keterbatasan dan kemungkinan komplikasi paska
bedah patut diketahui oleh ortodontis. Perawatan
orto lanjutan ditujukan untuk mencapai hasil akhir
perawatan yang optimal.3
TINJAUAN PUSTAKA
Definisi Bedah Ortognatik
Bedah ortognatik adalah prosedur
pembedahan yang dirancang untuk memperbaiki
deformitas muskulusskeletal, dento-osseus dan
jaringan lunak pada rahang serta struktur lainnya
yang berkaitan dengannya. Bedah ortognatik
dirancang untuk meluruskan kembali struktur
kerangka rahang atas dengan struktur kraniofasial
lainya.3
Bedah ortognatik dapat dilakukan di rahang
bawah atau rahang atas atau keduanya. Bedah
ortognatik dilakukan untuk mengoreksi
deformitas dentofasial. Tujuan bedah ortognatik
adalah memperbaiki profil dan fungsi oral,
terutama pada pasien dengan kelainan skeletal dan
dental yang parah.3
Klasifikasi Deformitas Dentofasial
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 41 – 45
42
Deformitas dentofasial dapat
diklasifikasikan sebagai berikut : (1) Maksila.
Maksila protrusif, yaitu pertumbuhan yang
berlebih dalam arah horisontal, terkadang disertai
protrusi mandibula.. (2) Defisiensi
anteroposterior (AP) maksila. Pertumbuhan
maksila yang tidak adekuat dalam arah anterior.
(3) Kelebihan Maksila Vertikal. Pertumbuhan
berlebih maksila dalam arah inferior akan
memberikan penampakan gigi dan gingiva yang
berlebih. (4) Defisiensi Maksila Vertikal. Gigitan
dalam, wajah bagian bawah pendek. (5) Defisiensi
Maksila Transversal. Etiloginya adalah
kongenital, traumatik dan iatrogenik. (6)
Defisiensi mandibula meliputi hyperplasia
mandibula, defisiensi /hypoplasia mandibula, dan
asimetri antero posterior mandibula. (7)
Gabungan deformitas maksila mandibula meliputi
brakhifasial, dolikofasial, dan apertognatia.5
Indikasi Bedah Ortognatik
Bedah ortognatik dapat dilakukan pada
empat keadaan spesifik sebagai berikut : (1)
perbaikan posisi dental yang sulit dicapai dengan
perawatan ortodonti saja, karena malposisi yang
parah. (2) pola skeletal yang buruk untukk
dikoreksi secara ortoodonti. (3) hanya dengan
perawatan ortodonti saja tidak dapat diperoleh
estika fasial yang serasi. (4) hanya dengan
perawatan ortodonti tidak dapat dicapai oklusi
fungsional.4,5
Kontra Indikasi Bedah Ortognatik
Jika kondisi kesehatan umum tidak
memadai, keluhan ringan, atau pasien berusia
muda . Pada pasien muda dianjurkan untuk
menuggu sampai pertumbuhan selesai.4,5
Diagnosis dan Perencanaan Perawatan
Agar dapat memberikan perawatan yang
tepat bagi pasien saat mengkoreksi deformitas
dentofasial, ahli bedah rahang dan ortodontis
harus mempunyai interaksi dan komunikasi yang
baik, serta mampu untuk mendiagnosa secara
tepat deformitas yang terjadi, menyusun rencana
perawatan yang komprehensif dan melaksanakan
perawatan.3-5
Prosedur Paska Bedah Ortognatik
Ada beberapa prosedur yang perlu
diperhatikan paska bedah ortognatik :3-5
1. Hospitalisasi. Lamanya hospitalisasi
tergantung dari jenis operasi yang dilakukan
(operasi dua rahang memerlukan waktu lebih
lama dibandingkan operasi satu rahang).
2. Medikasi. Medikasi yang diberikan adalah
pemberian antibiotik, analgesik dan anti
inflamasi.
3. Pemeriksaan klinis, yaitu analisis jaringan
lunak. Analisis jaringan lunak terdiri atas
analisis estetik fasial, analisis penampakan
depan, analisis profil, pemeriksaan intra oral
pada berbagai sisi dan sendi
temporomandibular. Keseluruhan wajah
dibagi menjadi tiga bagian yang sama yaitu
sepertiga bagian atas, tengah dan bawah.
Apabila terdapat perubahan dalam
proporsionalitas fasial, hal ini mudah terlihat.
(1) Papillary plane harus paralel dengan lantai.
(2) Plane of ear sejajar lantai. (3) Frankfurt
Horizontal Plane, yaitu garis yang ditarik dari
tragus telinga ke tonjolan tepi infraorbital
harus sejajar dengan lantai. Pada analisis
penampakan depan, yang perlu diperhatikan
adalah kesimetrisan mata, hidung, dahi. Pada
pemeriksaan intra oral, hal-hal yang perlu
diketahui antara lain hubungan oklusal, kurva
Wilson dan kurva spee.3,5-8
4. Postsurgical records. Untuk mengetahui ada
atau tidaknya komplikasi dan sebagai rekam
medik, setelah prosedur bedah, perlu
dilakukan evaluasi radiografis yaitu lateral
cephalometri, panoramic, evaluasi oklusi dan
artikulasi, pencatatan oklusal dan
neurosensory. Analisis sefalometrik
merupakan cara yang dapat diandalkan untuk
ke pasien perubahan yang terjadi setelah
pembedahan.3,5-8
5. Profil jaringan lunak. Perlu diperhatikan
harmonisasi komponen dental skeletal dan
jaringan lunak.
6. Pemberian makanan lunak. Pasien
diinstruksikan untuk makan makanan lunak 2-
6 minggu paska operasi.
7. Kontrol teratur sehingga ahli bedah rahang
dapat memantau proses penyembuhan. Pada
saat fiksasi dilepas, sangat penting bagi
ortodontis untuk melakukan kontrol.
8. Setelah 6 minggu, pasien dapat mulai makan
makanan padat
9. Setelah 3 bulan paska operasi, pasien sudah
dapat melakukan aktivitas fisik seperti
sediakala. Perawatan ortodonti paska bedah
dapat dilakukan setelah tercapai stabilitas.5-7
Perawatan Ortodonti Paska Bedah
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 41 – 45
43
Perawatan ortodonti yang dilakukan paska
bedah ortognatik mempunya tujuan untuk
menyempurnakan perawatan ortodonti dan bedah
ortognatik yang telah dilakukan serta memperoleh
interdigitasi yang baik. Agar perawatan ortodonti
ini dapat berhasil, ortodontis harus melakukan
evaluasi pasien dengan cermat, sekitar satu
minggu paska bedah untuk mengetahui oklusi dan
stabilitas paska bedah.8,9
Secara umum, perawatan ortodonti paska
bedah meliputi perbaikan komponen-komponen
alat ortodonti seperti koordinasi archwire,
prosedur rutin perawatan ortodonti dan retensi.
Respon skeletal dan dental setelah prosedur bedah
ortognatik perlu juga diperhatikan. Stabilitas
skeletal paska bedah mempengaruhi besarnya
pergerakan gigi yang dilakukan pada perawatan
ortodonti lanjutan. 5,8,9
Setelah tercapai stabilitas paska operasi,
sekitar 4 minggu, perawatan ortodonti dapat mulai
dilakukan. Alat-alat fiksasi dilepas dan digantikan
dengan kawat aktif untuk menggerakkan gigi ke
posisi yang diinginkan. Kawat yang digunakan
adalah kawat yang lentur (stainless steel .016,
coaxial, beta titanium wire (TMA) sehingga
memiliki gayang yang ringan. Pada tahap ini juga
digunakan elastic box/vertical untuk membantu
fikasis rahang. Elastik dipakai pasien secara terus
menerus termasuk pada saat makan selama 4
minggu pertama. Kemudian elastik dipakai terus
menerus kecuali saat makan selama 4 minggu
kedua, dan diteruskan hanya dipakai pada malam
hari selama 3-4 minggu berikutnya. Apabila
oklusi sudah stabil, pemakaian elastik dapat
dihentikan.5-10
Penggunaan alat retensi pada perawatan
ortodonti paska bedah ortognatik tidak berbeda
dengan pasien ortodonti pada umumnya.
Disarankan retensi dilakukan minimal dua tahun
setelah perawatan ortodonti selesai untuk
mengetahui stabilitas jangka panjang dari
perawatan ortodonti.5-8
Stabilitas Paska Bedah Ortognatik
Stabilitas paska bedah sangat penting bagi
ortodontis karena mempengaruhi perawatan
ortodonti yang akan dilakukan. Ada beberapa hal
yang mempengaruhi stabilitas paska bedah
ortognatik, yaitu :5-9
1. Mobillisasi jaringan lunak. Setelah bedah
ortognatik, jaringan lunak (periosteum,
ligament, otot-otot dan jaringan submucosa
yang ikut teregang akan cenderung untuk
kembali ke posisinya semula sehigga perlu
dipertimbangkan juga besarnya reposisi yang
akan dilakukan.
2. Besarnya reposisi yang dilakukan. Perubahan
paska bedah merupakan multifaktorial
fenomena. Adanya variasi individual dan
besarnya pergerakan yang dilakukan dalam
prosedur bedah mempengaruhi stabilitas hasil
perawatan.
3. Metode fiksasi. Penting bagi ahli bedah mulut
untuk mendiskusikan dengna ortodontis tehnik
fikasis yang akan digunakan. Ada tiga tehnik
fikasi yaitu :
a. Total rigid fixation (anterior and posterior
plates). Seluruh segmen difiksasi dengan
menggunakan plas dan screw sehingga
peran ortodontis paska bedah terbatas pada
perawatan ortodonti.
b. Anterior rigid fixation with posterior
suspension wires. Segmen anterior
difiksasi dengan menggunakan plat dan
screw, sedangkan pada segmen posterior
menggunakan suspension wires secara
bilateral. Pada tehnik ini, segmen posterior
masih dapat bergerak.
c. Infraorbital suspension wires. Apabila
infraorbital suspension wires digunakan
untuk stabilisasi skeletal perawatan orto
paska bedah segera dilakukan setelah
oklusal splint dilepaskan. Spesialis bedah
mulut akan melepaskan suspension wires,
sedangkan splint wire pada gigi rahang atas
tetap ada. Peran ortodontis adalah
melepaskan splind dan segera melakukan
perawatan ortodonti.
d. Peran ortodontis, menghilangkan
kompensasi dental, koreksi diskrepansi
gigi, leveling rahang atas dan rahang
bawah, dan koreksi diskrepansi transversal.
PEMBAHASAN
Selama dua dekade terakhir, intervensi
bedah ortognatik dalam merawat deformitas
skeletal telah banyak dilakukan. Kombinasi
perawatan ortodonti dan bedah memberikan hasil
yang lebih baik dalam merawat pasien dengan
skeletal dan dental displasia.1-3
Tujuan dari bedah ortognatik adalah
memperbaiki deformitas skeletal, estetika, dan
oklusi. Penatalaksanaan pasien secara
menyeluruh tergantung pada evaluasi dan
diagnosa deformitas. Untuk menegakkan
diagnosis dan merencanakan perawatan yang
tepat, diperlukan pengetahuan yang mendalam
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 41 – 45
44
mengenai pertumbuhan dan perkembangan kranio
dentofasial, biomekanika pergerakan gigi, model
studi, foto fasial, foto intraoral dan foto ronsen
panoramik.1-5
Potensi relaps setelah bedah ortognatik
menjadi bahasan penting dimana perlu
diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi
stabilitas skeletal paska bedah ortognati. Tipe
fiksasi dan besarnya pergerakan yang dilakukan
dalam operasi bedah turut mempengaruhi
kestabilan bedah ortognatik. Selain itu,
keberhasilan koreksi bedah tergantung dari
stabilitas serta respon skeletal dan dental setelah
perawatan bedah ortognatik.5-8
Paska bedah ortognatik, penting bagi
ortodontis melakukan evaluasi, observasi dan
melanjutkan perawatan akhir. Adanya
keterbatasan dan kemungkinan komplikasi paska
bedah patut diketahui oleh ortodontis. Perawatan
orto lanjutan ditujukan untuk mencapai hasil akhir
perawatan yang optimal.3
Perawatan ortodonti yang dilakukan
paska bedah ortognatik mempunya tujuan untuk
menyempurnakan perawatan ortodonti dan bedah
ortognatik yang telah dilakukan serta memperoleh
interdigitasi yang baik. Agar perawatan ortodonti
ini dapat berhasil, ortodontis harus melakukan
evaluasi pasien dengan cermat, sekitar satu
minggu paska bedah untuk mengetahui oklusi dan
stabilitas paska bedah.6-9
Peran ortodontis, menghilangkan
kompensasi dental, koreksi diskrepansi gigi,
leveling rahang atas dan rahang bawah, dan
koreksi diskrepansi transversal. Secara umum,
perawatan ortodonti paska bedah meliputi
perbaikan komponen-komponen alat ortodonti
seperti koordinasi archwire, prosedur rutin
perawatan ortodonti dan retensi. Respon skeletal
dan dental setelah prosedur bedah ortognatik perlu
juga diperhatikan. Stabilitas skeletal paska bedah
mempengaruhi besarnya pergerakan gigi yang
dilakukan pada perawatan ortodonti lanjutan. 2-12
Setelah tercapai stabilitas paska operasi,
sekitar 4 minggu, perawatan ortodonti dapat mulai
dilakukan. Alat-alat fiksasi dilepas dan digantikan
dengan kawat aktif untuk menggerakkan gigi ke
posisi yang diinginkan. Kawat yang digunakan
adalah kawat yang lentur (stainless steel .016,
coaxial, beta titanium wire (TMA) sehingga
memiliki gaya yang ringan. Pada tahap ini juga
digunakan elastic box/vertical untuk membantu
fikasis rahang. Elastik dipakai pasien secara terus
menerus termasuk pada saat makan selama 4
minggu pertama. Kemudian elastik dipakai terus
menerus kecuali saat makan selama 4 minggu
kedua, dan diteruskan hanya dipakai pada malam
hari selama 3-4 minggu berikutnya. Apabila
oklusi sudah stabil, pemakaian elastik dapat
dihentikan.2,5-13
Penggunaan alat retensi pada perawatan ortodonti
paska bedah ortognatik tidak berbeda dengan
pasien ortodonti pada umumnya. Disarankan
retensi dilakukan minimal dua tahun setelah
perawatan ortodonti selesai untuk mengetahui
stabilitas jangka panjang dari perawatan
ortodonti.12
KESIMPULAN
Diperlukan kerjasama yang baik antara ahli bedah
mulut dan ortodontis dalam menangani pasien
paska bedah ortogantik. Stabilitas perawatan
paska bedah sangat penting karena akan
mempengaruhi perawatan ortodonti paska bedah.
Perawatan ortodonti paska bedah dilakukan
apabila kondisi pasien sudah stabil. Ortodontis
harus memahami segala hal tentang perawatan
ortodonti paska bedah dan hal-hal yang dapat
mempengaruhi stabilitas perawatan.
DAFTAR PUSTAKA
1. John BP, Richard AS. Skeletal and dental
responses to orthognathic surgical treatment.
Angle Ortho 1997;67(6): 447-454.
2. William RP, L Tanya JB, Ceib P. Long-term
stability of surgical open bite correction by Le
Fort I Osteotomy. Angle Ortho 2000;70(2):
112-117.
3. Bishara SE. Textbook of Orthodontics. WB
Saunders CO, St.Louis 2001; 550-560.
4. Proffitt WR, Fields HR. Contemporary
orthodontics. 4th Ed. St.Louis, Missouri :
Mosby Elsevier; 2007; 705-718.
5. Epker BN, Stella JP, Fish LC. Dentofacial
Integrated Orthodontic and Surgical
Correction. 2nd Ed. Mosby Year Book Inc. St
Louis. 1986; 138, 146-157, 155-157, 178.
6. Paul AD, Lisen E, Leiv. LeFort I maxillary
advancement 3 year stability and risk factors
for relapse. AJODO 2005. 128: 556-7.
7. Bailey LJ, Cavidanes, LHS. Stability and
Predictability of Orthognathic Surgery.
AJODO. June, 2004.
8. Moyes RE. Handbook of Orthodontics. 4th Ed
Year Book Medial Pub Inc. 1988. 497-510.
9. Harry LL. Scott C. Biomechanical factors in
surgical orthodontics. In Nanda R.
Biomechanic and Esthetic Strategies in
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 41 – 45
45
Clinical Orthodontics. Philadelphia. WB
Saunders. 2005: 310-327.
10. Rakosi T, Jonas I, Graber TM. Color atlas of
dental medicine-orthodontic diagnosis.
Stuttgart; Georg Thieme Verlag: 1993. 256-80.
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 46 – 52
46
Potensi Ekstrak Daun Dandang Gendis (Clinacanthus nutans) untuk Mempercepat
Penyembuhan Luka di Rongga Mulut
(Tinjauan Pustaka)
Moehamad Orliando Roeslan
Staf Pengajar Bagian Histologi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trsakti
ABSTRACT
Background: Clinacanthus nutans (C. nutans) is a plant that is easily found in South-East Asia.
Traditionally, this plant has been used for treatment of snake bite, cancer, and diabetes. In addition,
leaves extract of C. nutans have been investigated and biological activity of this plant has potentially
support wound healing in the oral cavity. Objectives: The aim of this review is to help researchers and
clinicians to understand the reason why C. nutans has potential as a drug to accelerate wound healing
in oral cavity. Literature review: Wound healing is a complex process that is regulated by cellular,
humoral and molecular mechanism. The main aim of wound healing is regeneration and repair. Wound
healing depends on many factors including cells, growth factor, and cytokines. Wound healing also
has phases: inflammation phase, proliferation phase and remodelling phase. C. nutans is known to
contain anti-inflammatory, antivirus, antioxidant, antibacteria, and analgesic. Wound healing agents
must have the ability of anti-inflammation, antivirus, antioxidant, antibacteria and analgesic. The anti-
inflammatory activity of C. nutans is expected to shorten inflammation phase in wound healing, so the
wound will heal faster. Antibacteria activity of C. nutans can prevent infection during wound healing.
Antioxidant activity of C. nutans is also needed to prevent damage of healthy tissue from reactive
oxygen species (ROS). However, there is no research on the effect of C. nutans on osteoblast
proliferation, which has role to restore bone density after tooth extraction. Conclusion: C. nutans have
a lt of the biological activity needed to accelerate wound healing in oral cavity.
Keyword: Clinacanthus nutans, wound healing, oral cavity
PENDAHULUAN
Di negara berkembang, penggunaan
tanaman untuk pengobatan masih digunakan oleh
sebagian besar masyarakatnya. Hal ini mungkin
karena obat-obatan masih terlalu mahal dan
aksesnya yang sulit bagi masyarakat yang tinggal
di pedalaman. Namun seiring berjalannya waktu,
masyarakat perkotaan pun sekarang banyak yang
memilih menggunakan obat tradisional. Salah
satu alasannya adalah obat tradisional dianggap
mempunyai efek samping yang lebih sedikit
dibanding obat konvensional. Karena alasan itu
pula obat tradisional berkontribusi hingga 50%
terhadap perkembangan obat konvensional yang
ada di pasaran sejak tahun 1981 hingga 2014.1
Clinacanthus nutans (C. nutans/Dandang
Gendis) adalah tanaman yang banyak tumbuh di
Asia. Untuk negara-negara di Asia Tenggara
sendiri, tumbuhan ini sudah banyak digunakan
sebagai obat. Di Thailand, ektrak daun ini
digunakan sebagai obat tradisional ruam kulit,
gigitan serangga, virus herpes simpleks dan
varicella-zoster.2 Di Malaysia, ekstrak daun ini
banyak ditemukan dijual bebas untuk mengobati
kanker. Sedangkan di Indonesia sendiri, ekstrak
daun C. nutans banyak digunakan untuk
pengobatan diabetes dan disentri secara
tradisional.
C. nutans adalah nama yang dikenal di
Indonesia, sedangkan di Malaysia popular dengan
nama “Sabah snake grass” atau “Belalai Gajah”.
Di Thailand, dikenal dengan “phaya yo” atau
“phaya plongtong”. Di Vietnam dengan nama
“Bim Bip,” “Xuong Khi,” atau “Manh Cong”,
sedangkan masyarakat China mengenal tumbuhan
ini dengan nama “e zui hua” or “you dun cao”.3, 4
Tinggi tumbuhan C. nutans mencapai sekitar 1-3
meter. Daun dari dandang gendis berwarna hijau,
berbentuk menyirip, panjangnya berkisar 8-12 cm
dan lebar antara 4-6 cm. Tumbuhan ini juga
mempunyai bunga yang ada di atas bagian
percabangan. Berikut adalah klasifikasi taxonomi
tumbuhan C. nutans:
Nama ilmiah : Clinacanthus nutans (Burm.f.)
Lindau
Famili : Acanthaceae
Genus : Clinacanthus
Species : C. nutans
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 46 – 52
47
Tumbuhan C. nutans dilaporkan memiliki
berbagai variasi phenolic, terpenoid dan beberapa
molekul murni seperti benzenoid,
glycoglycerolipids, glycosylglycerides, turunan
klorofil, asam lemak, fitosterol, cerebrosides.
stigmasterol, lupeol, β-sitosterol. vitexin
(apigenin/8-beta-D-glucopyranosyl-5,7dihydroxy
-2-(4hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one) ,
isovitexin (saponaretin /6-beta-D-
glucopyranosyl-4',5,7-trihydroxyflavone),
schaftoside (shaftoside), isomollupentin 7-O-b-
glucopyranoside, orientin (lutexin/luteolin),
isoorientin (homoorientin/luteolinn6-C-beta-D-
glucopyranoside), clinacoside A, clinacoside B,
clinacoside C, cycloclinacoside A1,
cycloclinacoside A2, 13-hydroxy-(13-S)-
phaeophytin b, pupurin-18-phytyl ester, dan
pheophorbide. 2 5-8 Dari seluruh molekul murni
yang berhasil diisolasi dari C. nutans, hanya
molekul chlorophyll related yang sudah terbukti
secara ilmiah mempunyai aktivitas biologis, yaitu
antivirus terhadap virus herpes simpleks.9
TINJAUAN PUSTAKA
Aktivitas biologis C. nutans
Dari penelitian terdahulu, baik in vivo
maupun in vitro, ekstrak daun C. nutans diketahui
mempunyai kemampuan antivirus, antioksidan,
antikanker, antiinflamasi, antibakteri, dan
analgesik.10-15 Di Thailand, obat yang berasal dari
ekstrak daun C. nutans untuk mengobati herpes
simpleks sudah dijual secara komersil dengan
harga yang jauh dibawah harga obat
konvensional.
Ekstrak etanol menunjukkan inhibisi
terhadap produksi peroksida yang diproduksi oleh
makrofag tikus setelah distimulasi oleh phorbol
myristate acetate (PMA). Ekstrak ini juga
mempunyai efek proteksi terhadap sel darah
merah tikus yang diinduksi oleh 2,2′-azobis (2-
amidinopropane) hydrochloride (AAPH).12
Kemampuan antikanker C. nutans sudah diteliti
dengan menggunakan berbagai galur sel. Dalam
penelitian sitotoksisitas C. nutans, diketahui
tumbuhan ini mempunyai kemampuan
antiproliferasi dan antikanker terhadap berbagai
galur sel. Penelitian yang dilakukan juga
menggunakan berbagai ekstrak yang berbeda
(non-polar, semipolar dan polar). Ekstrak
kloroform, metanol dan air menunjukkan
kemampuan antiproliferasi terhadap human liver
hepatocellular carcinoma (HepG2), human
neuroblastoma cell line (IMR-32), human lung
cancer cell line (NCI-H23), human gastric cancer
cell line (SNU-1), human colon adenocarcinoma
cell line (LS-174T), human erythroleukemia cell
line (K-562), human cervical cancer cell line
(HeLa), dan human Burkitt's lymphoma cell line
(Raji). Ekstrak C. nutans juga tidak menunjukkan
toksisitas terhadap sel HUVEC (human umbilical
veins endothelial cell), hal ini membuktikan
bahwa C. nutans aman terhadap sel normal.16
Pada penelitian terdahulu ekstrak metanol
dievaluasi dengan menggunakan model oedem
tikus yang diinduksi dengan carrageenan dan
ethyl phenylpropiolate (EPP). Penelitian ini
menunjukkan aktivitas anti-inflamasi melalui
efek inhibisi fungsi respon netrofil tanpa adanya
efek toksisitas yang signifikan.17
Kemampuan antibakteri C. nutans
menunjukkan hasil positif ketika diuji terhadap
bakteri S. aureus, E. coli, P. acnes, S. epidermis
dan B. cereus. Hal ini mungkin berhubungan
dengan lupeol, β-sitosterol, flavonoid, dan
terpenoid yang terkandung di dalam C. nutans.18-
20 Aktivitas analgesik tumbuhan ini diinvestigasi
dengan menggunakan ekstrak butanol. Hasilnya
menunjukkan C. nutans memiliki aktivitas
analgesik yang menyerupai aspirin.10
Secara tradisional, di Thailand dan
Malaysia bagian pedalaman tumbuhan ini sudah
digunakan sebagai obat untuk mengobati gigitan
ular atau kalajengking. Namun setelah dilakukan
penelitian, tidak ditemukan adanya aktivitas
antivenin di C. nutans.21 Ekstrak etanol bagian
daun dan batang tumbuhan C. nutans mempunyai
kemampuan anti-dengue pada penelitian yang
dilakukan dengan menggunakan galur sel Huh-7.8
Penelitian C. nutans sebagai penyembuh
luka juga sudah dilakukan. Salah satunya adalah
penelitian in vitro dengan menggunakan human
gingival fibroblast (HGF) untuk melihat efek
ekstrak kloroform dan heksana C. nutans terhadap
kecepatan migrasi HGF dengan teknik scratch
assay. Hasilnya menunjukkan bahwa kedua
ekstrak pada dosis 10 g/ml mempercepat migrasi
HGF dibandingkan dengan grup lain.22 Hal ini
membuktikan bahwa dengan dosis seminimal 10
g/ml, Dandang Gendis mampu menginduksi
migrasi HGF.
Selain itu, tumbuhan ini juga sudah
dilakukan uji klinik mengevaluasi pengobatan
terhadap stomatitis aftosa dengan metode double
blind controlled trial terhadap 43 subyek.
Hasilnya, ekstrak C. nutans menunjukkan
penyembuhan yang lebih baik dibanding plasebo,
namun triamcinolone acetonide lebih baik dari
ekstrak C. nutans.23
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 46 – 52
48
Kombinasi C. nutans dan Elephantopus
scaber juga sudah diteliti untuk penyembuhan
luka pada kulit tikus. Fraksi etil asetat
menunjukkan hasil positif pada luka eksisi dan
insisi, sedangkan fraksi air memperlihatkan hasil
yang positif pada luka bakar. Dari hasil LC-MS
diketahui adanya beberapa molekul berbasis
flavonoid yang bekerja secara sinergi.24
Tulisan ini akan mengulas potensi
kemampuan C. nutans untuk mempercepat
penyembuhan luka di rongga mulut berdasarkan
penelitian-penelitian yang sudah dilakukan secra
in vitro dan in vivo.
Proses penyembuhan luka
Penyembuhan luka adalah proses
menggantikan struktur selular dan jaringan yang
rusak melalui tahap yang kompleks dan dinamis.
Terdiri atas berbagai proses biokimia yang
terorganisir untuk memperbaiki jaringan yang
rusak. Pada orang dewasa, penyembuhan luka
dapat dibagi menjadi tiga fase, yaitu fase
inflamasi, proliferasi dan remodeling.25
Fase inflamasi mulai segera setelah terjadi
luka, yang diawali dengan mekanisme hemostasis
yang bertujuan untuk menghentikan pendarahan.
Karakteristik yang khas pada tahap ini adalah
vasokonstriksi dan agregasi platelet untuk
menginduksi vasodilatasi dan fagositosis,
sehingga terjadi inflamasi di daerah luka. Fase
berikutnya adalah fase proliferasi.26 Ciri khas fase
proliferasi adalah granulasi, kontraksi luka, dan
epitelisasi. Selama proses granulasi, fibroblas
membentuk dasar kolagen yang diikuti oleh
produksi kapiler baru.26 Selama kontraksi luka,
myofibroblas memperkecil ukuran luka dengan
dengan mencengkeram daerah pinggir luka dan
berkontraksi dengan cara sama seperti yang
dilakukan oleh otot polos. Setelah tugas sel ini
hampir selesai, sel-sel yang tidak dibutuhkan akan
apoptosis.27 Epitelisasi melibatkan proliferasi sel
epitel, yang akan memanjat ke atas daerah luka,
menutupi jaringan baru yang terbentuk.
Angiogenesis
Pembentukan pembuluh darah baru
(angiogenesis) sangat penting dalam proses
penyembuhan luka dan terjadi secara bersamaan
dengan semua tahap proses perbaikan.28 Tahap
pertama pada pembentukan pembuluh darah baru
adalah perlekatan faktor pertumbuhan dengan
reseptor nya masing-masing pada sel endotel
pembuluh yang ada. Sel endotel yang teraktivasi
mensekresi enzim proteolitik untuk melarutkan
lamina basal, sehingga sel endotel dapat
berproliferasi dan migrasi ke daerah luka. Untuk
dapat membuka ruang untuk sel berproliferasi,
membran basalis dan matriks ekstraselular
terdegradasi. Proses ini dikenal dangan
sprouting.29, 30
Angiogenesis distimulasi oleh faktor
pertumbuhan dan hipoksia jaringan.31
Lingkungan hipoksia terjadi karena adanya
penutupan permukaan luka oleh bekuan fibrin.
Penutupan permukaan luka sangat diperlukan
untuk membentuk lingkungan hipoksia luka.
Bekuan fibrin yang terbentuk selama hemostasis
menyediakan penutupan sementara sehingga
angiogenesis dapat berlangsung. Lingkungan
hipoksia juga menginduksi makrofag mensekresi
faktor angiogenesis seperti fibroblast growth
factor (bFGF or FGF-2) dan acidic FGF (aFGF
atau FGF-1) yang dilepaskan segera setelah
adanya gangguan sel.32, 33
Fase terakhir adalah fase remodeling yang
akan berlangsung selama beberapa bulan. Selama
proses ini kolagen dan matriks protein akan terus
disintesis agar daerah luka kembali seperti
sediakala. Tujuan utama penyembuhan luka
adalah untuk mempercepat waktu penyembuhan
atau untuk meminimalisir efek samping yang
mungkin akan terjadi.10
Parameter yang digunakan untuk menilai
aktivitas penyembuhan luka:
1. Parameter fisik
Karakteristik fisik seperti kompresi luka,
epitelisasi, dan bekas luka dapat diamati
dengan mengukur penutupan luka dan
mencatat perubahan fisik bekas luka.34
2. Parameter mekanis
Kemampuan mekanis seperti kualitas
kerapuhan dan elastisitas dapat diamati dengan
mengukur kekuatan yang dibutuhkan untuk
merusak luka atau jaringan.35
3. Parameter biokimia
Kolagen berkontribusi sangat besar dalam
menentukan kualitas penyembuhan luka.
Asam amino di kolagen, yaitu hydroxyproline,
dapat dievaluasi untuk menentukan jumlah
kolagen di luka dengan cara teknik
calorimetric, spectrometric atau
chromatographic.36
4. Parameter histologis
Pengecekan kualitas secara histologis,
mengevaluasi komponen sel dan
jumlahkandungan kolagen adalah parameter
yang penting dalam pemulihan luka.37
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 46 – 52
49
Faktor-faktor yang mempengaruhi
penyembuhan luka:
1. Diet
Penyembuhan luka adalah proses
anabolik yang membutuhkan energi dan
nutrisi. Kandungan serum albumin sebanyak
3,5 g/dl atau lebih dibutuhkan untuk
penyembuhan yang baik.38 Protein juga
penting untuk sintesis kolagen di
daerah luka. Keadaan malnutrisi dapat
menyebabkan jumlah protein yang kurang
yang akhirnya dapat menimbulkan penurunan
sintesis kolagen yang bisa meningkatkan
resiko terkena infeksi.39
2. Infeksi di daerah luka
Penyebab paling umum lamanya waktu
penyembuhan luka adalah infeksi di daerah
luka.40 Staphylococcus aureus, Streptococcus
pyogenes, Corynebacterium sp., Escherichia
coli dan Pseudomonas aeruginosa adalah
organisme yang sering menyebabkan infeksi
luka.41
3. Oksigen yang kurang dan perfusi jaringan di
daerah luka
Pasokan darah yang cukup dan perfusi
jaringan sangat penting untuk penyembuhan
luka. Rasa sakit yang berlebihan, demam atau
anxiety dapat menyebabkan vasokonstriksi
secara lokal dan memperlama penyembuhan.42
Merokok dan penggunaan tembakau
menurunkan perfusi jaringan dan tekanan
oksigen di daerah luka.41
4. Obat-obatan
Obat-obatan kemoterapi yang digunakan
dalam pengobatan kanker dapat memperlama
penyembuhan luka.43 Glukokortikoid sistemik
dapat mengganggu proses penyembuhan luka
dengan menurunkan sintesis kolagen dan
proliferasi fibroblas.
5. Usia lanjut
Usia lanjut sering dihubungkan dengan
tertundanya penyembuhan luka. Dilaporkan
bahwa pertumbuhan dan aktivitas fibroblas
berkurang, dan sintesis kolagen dan kontraksi
luka menjadi lambat pada individu yang lanjut
usia.44
6. Diabetes dan kondisi lainnya
Penderita diabetes lebih rentan terkena
infeksi luka. Dalam penelitian ditemukan
bahwa resiko infeksi pada luka meningkat
hingga 11% pada penderita diabetes.45
Penyakit liver akut dan kronis juga
dihubungkan dengan tertundanya
penyembuhan luka.46
PEMBAHASAN
Respon inflamasi akut pada saat fase awal
terjadinya luka akan merangasang faktor-faktor
penting yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan
perbaikan jaringan. Faktor-faktor tersebut antara
lain sitokin dan chemokines.47 Fase inflamasi yang
berkepanjangan dapat mencegah luka masuk ke
fase remodeling. Akhirnya, penutupan luka akan
tertunda dan rasa sakit akan timbul, yang akan
mengarah ke terhalangnya proses
penyembuhan.48 Oleh karena itu, terapi dengan
obat yang mempunyai kemampuan anti-inflamasi
menjadi perhatian para peneliti, dengan tujuan
untuk meningkatkan kenyamanan pasien pada
saat proses penyembuhan luka.49 Dengan adanya
kemampuan anti-inflamasi dalam obat
penyembuh luka, maka diharapkan fase inflamasi
menjadi lebih singkat, sehingga luka dapat
sembuh lebih cepat. Ekstrak C. nutans sudah
diteliti mempunyai kemampuan anti-inflamasi
secara in vivo,17 hal ini bisa menjadi kemampuan
positif yang dibutuhkan dalam penyembuh luka.
Infeksi adalah faktor penting yang dapat
mengganggu penyembuhan luka.50 Mengurangi
adanya bakteri yang ada di daerah luka adalah hal
penting yang dibutuhkan untuk penyembuhan
luka yang lebih baik. Obat yang ideal untuk
mencegah terjadinya infeksi luka adalah obat
yang mempunyai kemampuan sebagai
antimikrobial dan sekaligus bertindak sebagai
stimulan aktivitas respon imun secara natural
tanpa merusak jaringan sehat sekitarnya.51
Ekstrak C. nutans mempunyai kemampuan
antibakteri18 dan mampu memodulasi proliferasi
limfosit dan sel PMN.52 Kedua kemampuan ini
adalah aktivitas yang sangat positif dalam
mencegah terjadinya infeksi dan mempercepat
penyembuhan luka.
Masuknya netrofil ke daerah luka akan
menimbulkan respiratory burst dan menghasilkan
radikal bebas. Adanya radikal bebas akan
menyebabkan stres oksidatif yang kemudian
mengarah ke peroksidasi lipid, kerusakan DNA
dan inaktivasi enzim. Enzim ini termasuk enzim
scavenger radikal bebas yang berfungsi
membatasi efek reactive oxygen species (ROS).
Oleh karena itu dibutuhkan antioksidan yang
dapat mengurangi efek ROS, sehingga
meningkatkan efisiensi penyembuhan luka.53
Ekstrak daun C. nutans mempunyai aktivitas
biologis sebagai antioksidan.16 Aktivitas ini akan
sangat dibutuhkan untuk mencegah kerusakan
jaringan sehat yang lebih lanjut yang disebabkan
oleh ROS.
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 46 – 52
50
Pada penyembuhan luka soket pasca
pencabutan gigi tidak hanya melibatkan jaringan
lunak, tetapi juga jaringan keras, yaitu tulang.
Pada keadaan tanpa stimulasi, osteoblas akan
teraktivasi pada hari ke-1 sampai ke-3 pasca
pencabutan gigi dan osteoid akan terbentuk dalam
seminggu. Untuk menyatukan celah soket dengan
tulang primer dibutuhkan waktu 4 sampai 6
minggu tergantung besarnya soket.54 Sampai saat
ini belum ada penelitian yang meneliti efek
ekstrak daun C. nutans terhadap proliferasi
osteoblas dan pembentukan tulang. Selain itu,
efek ekstrak daun C. nutans terhadap sel endotel
untuk merangsang terjadinya angiogenesis juga
belum diteliti.
KESIMPULAN
Kemampuan ekstrak C. nutans untuk
penyembuhan luka di rongga mulut perlu
diinvestigasi labih dalam lagi, Khususnya efek
terhadap osteoblas dan sel endotel, yang keduanya
mempunyai peran penting dalam penyembuhan
luka. Selain itu, penelitian yang mendalam sampai
tahap molekuler juga perlu dilakukan, agar
mekanisme efek ekstrak C. nutans terhadap
penyembuhan luka dapat dijelaskan.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa
obat untuk penyembuhan luka pasca pencabutan
gigi harus memiliki kemampuan antibakteri, anti-
inflamasi, antioksidan. Ekstrak daun C. nutans
memiliki semua kemampuan ini, namun demikian
masih diperlukan penelitian lebih lanjut yang
meneliti efek tumbuhan ini terhadap osteoblas dan
sel endotel.
DAFTAR PUSTAKA
1. Newman DJ, Cragg GM. Natural Products as
Sources of New Drugs from 1981 to 2014. J
Nat Prod 2016;79:629-661.
2. Sakdarat S, Shuyprom A, Dechatiwongse Na
Ayudhya T, Waterman PG, Karagianis G.
Chemical composition investigation of the
Clinacanthus nutans Lindau leaves. Thai J
Phytopharm 2008;13:13-24.
3. Panyakom K. Structural elucidation of
bioactive compounds of Clinacanthus nutans
(Burm. f.) Lindau leaves: Suranaree
University of Technology, Nakhon
Ratchasima; 2006.
4. Roosita K, Kusharto CM, Sekiyama M,
Fachrurozi Y, Ohtsuka R. Medicinal plants
used by the villagers of a Sundanese
community in West Java, Indonesia. J
Ethnopharmacol 2008;115:72-81.
5. Dampawan P, Huntrakul C, Reutrakul V.
Constituents of Clinacanthus nutans and the
crystal structure of lup-20(29)-ene-3-one. J
Sci Soc Thailand 1977;3:14-26.
6. Teshima K, Kaneko T, Ohtani K, Kasai R,
Lhieochaiphant S, Picheansoonthon C, et al.
Sulfur-containing glucosides from
Clinacanthus nutans. Phytochemistry
1998;48:831-835.
7. Teshima K., Kaneko T., Ohtani K., Kasai R.,
Lhieochaiphant S., Picheansoonthon C., et al.
C-Glycosyl Flavones from Clinacanthus
nutans. Nat Med 1997;51 (6):557.
8. Tu SF, Liu RH, Cheng YB, Hsu YM, Du YC,
El-Shazly M, et al. Chemical constituents
and bioactivities of Clinacanthus nutans
aerial parts. Molecules 2014;19:20382-
20390.
9. Sakdarat S, Shuyprom A, Pientong C,
Ekalaksananan T, Thongchai S. Bioactive
constituents from the leaves of Clinacanthus
nutans Lindau. Bioorganic & medicinal
chemistry 2009;17:1857-1860.
10. Satayavivad J, Bunyapraphatsara N,
Kitisiripornkul S, Tanasomwang W.
Analgesic and anti-inflammatory activities
of extract of Clinacanthus nutans (Burm.f.)
Lindau. Thai J Phytopharm 1996;3:
11. Sangkitporn S., Balachandra K., Bunjob M.,
Chaiwat S., Dechatiwongse Na Ayudhaya T.,
Jayavasu C. Treatment of herpes zoster with
Clinacanthus nutans (Bi Phaya Yaw) extract.
J Med Assoc Thai 1995;78:624-627.
12. Pannangpetch P., Laupattarakasem P.,
Veerapol Kukongviriyapan V.,
Kukongviriyapan U., Kongyingyoes B.,
Aromdee C. Antioxidant activity and
protective effect against oxidative hemolysis
of Clinacanthus nutans (Burm.f) Lindau.
Songklanakarin J Sci Technol 2007;29:1-9.
13. Jayavasu C, Dechatiwongse Na Ayudhaya T,
Balachandra K, Chavalittumrong P,
Jongtrakulsiri S. The virucidal activity of
Clinacanthus nutans Lindau extracts against
herpes simplex virus type-2: an in vitro
study. Bull Dept Med Sci 1992;34:153-158.
14. Huang D, Guo W, Gao J, Chen J, Olatunji
JO. Clinacanthus nutans (Burm. f.) Lindau
Ethanol Extract Inhibits Hepatoma in Mice
through Upregulation of the Immune
Response. Molecules 2015;20:17405-17428.
15. Arullapan S, Rajamanickam P, Thevar N,
Kodimani C. In Vitro Screening of
Cytotoxic, Antimicrobial and Antioxidant
Activities of Clinacanthus nutans
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 46 – 52
51
(Acanthaceae) leaf extracts. Trop J Pharm
Res, 2014;13:1455-1461.
16. Yong YK, Tan JJ, Teh SS, Mah SH, Ee GC,
Chiong HS, et al. Clinacanthus nutans
Extracts Are Antioxidant with
Antiproliferative Effect on Cultured Human
Cancer Cell Lines. Evidence-based
complementary and alternative medicine :
eCAM 2013;462751.
17. Wanikiat P, Panthong A, Sujayanon P,
Yoosook C, Rossi AG, Reutrakul V. The
anti-inflammatory effects and the inhibition
of neutrophil responsiveness by Barleria
lupulina and Clinacanthus nutans extracts. J
Ethnopharmacol 2008;116:234-244.
18. Dorman HJ, Deans SG. Antimicrobial agents
from plants: antibacterial activity of plant
volatile oils. J Appl Microbiol 2000;88:308-
316.
19. Kuete V, Kamga J, Sandjo LP, Ngameni B,
Poumale HM, Ambassa P, et al.
Antimicrobial activities of the methanol
extract, fractions and compounds from Ficus
polita Vahl. (Moraceae). BMC Complement
Altern Med 2011;11:6.
20. Singh B, Sahu PM, Sharma MK. Anti-
inflammatory and antimicrobial activities of
triterpenoids from Strobilanthes callosus
nees. Phytomedicine 2002;9:355-359.
21. Cherdchu C, Poopyruchpong N,
Adchariyasucha R, Ratanabanangkoon K.
The absence of antagonism between extracts
of Clinacanthus nutans Burm. and Naja naja
siamensis venom. Southeast Asian J Trop
Med Public Health 1977;8:249-254.
22. Roeslan M, Ayudhya T, Koontongkaew S.
Characteristics of Clinacanthus nutans
extraction from Thailand and Indonesia
(Preliminary Study). Sci-Health 2 2012;
23. Siriporn T. Clinical evaluation of
Clinacanthus nutans Lindau in orabase in the
treatment of ruccurent aphtous stomatitis.
Mahidol Dent J 2013;14(1):10-16.
24. Aslam MS, Ahmad MS, Mamat AS, Ahmad
MZ, Salam F. Antioxidant and Wound
Healing Activity of Polyherbal Fractions of
Clinacanthus nutans and Elephantopus
scaber. Evid Based Complement Alternat
Med: eCAM 2016;2016:4685246.
25. Flanagan M. The physiology of wound
healing. J Wound Care 2000;9:299-300.
26. Gantwerker EA, Hom DB. Skin: histology
and physiology of wound healing. Clin Plast
Surg 2012;39:85-97.
27. Kirsner RS, Eaglstein WH. The wound
healing process. Dermatol Clin 1993;11:629-
640.
28. Velnar T, Bailey T, Smrkolj V. The wound
healing process: an overview of the cellular
and molecular mechanisms. J Int Med Res
2009;37:1528-1542.
29. Reinke JM, Sorg H. Wound repair and
regeneration. European surgical research
Europaische chirurgische Forschung
Recherches chirurgicales europeennes
2012;49:35-43.
30. Robson MC, Steed DL, Franz MG. Wound
healing: biologic features and approaches to
maximize healing trajectories. Curr Probl
Surg 2001;38:72-140.
31. Giordano FJ, Johnson RS. Angiogenesis: the
role of the microenvironment in flipping the
switch. Curr Opin Genet Dev. 2001;11:35-
40.
32. Gurtner GC, Werner S, Barrandon Y,
Longaker MT. Wound repair and
regeneration. Nature 2008;453:314-321.
33. Strodtbeck F. Physiology of wound healing.
Newborn Infant Nurs Rev 2001;1:43-52.
34. Mustapha N. Glue as a Cell-Delivery Vehicle
in Wound Healing. J Trauma Treat
2015;4:250:
35. Casacó A, Fuente D, Ledon N, Ferandez A,
Crombet T. Anti- epidermal growth
factor/epidermal growth factor receptor
therapeutic anticancer drugs and the wound
healing process. J Cancer Sci Ther
2012;4:324-329.
36. Koyama Y. Effects of Collagen Ingestion
and their Biological Significance. J Nutr
Food Sci 2016;6:504:
37. Knott ME, Minatta JN, Roulet L, Gueglio G,
Pasik L, Ranuncolo SM, et al. Circulating
Fibroblast Growth Factor 21 (Fgf21) as
Diagnostic and Prognostic Biomarker in
Renal Cancer. J Mol Biomark Diagn 2016;1:
38. Hanna JR, Giacopelli JA. A review of wound
healing and wound dressing products. J Foot
Ankle Surg 1997;36:2-14; discussion 79.
39. Albritton JS. Complications of wound repair.
Clin Podiatr Med Surg 1991;8:773-785.
40. Lazarus GS, Cooper DM, Knighton DR,
Percoraro RE, Rodeheaver G, Robson MC.
Definitions and guidelines for assessment of
wounds and evaluation of healing. Wound
Repair Regen 1994;2:165-170.
41. LaVan FB, Hunt TK. Oxygen and wound
healing. Clin Plast Surg 1990;17:463-472.
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 46 – 52
52
42. Cuzzell JZ, Stotts NA. Wound care. Trial &
error yields to knowledge. Am J Nurs
1990;90:53-60, 63.
43. Franz MG, Steed DL, Robson MC.
Optimizing healing of the acute wound by
minimizing complications. Curr Probl Surg
2007;44:691-763.
44. Sherman RA. A new dressing design for use
with maggot therapy. Plast Reconstr Surg
1997;100:451-456.
45. Greenhalgh DG. Wound healing and diabetes
mellitus. Clin Plast Surg 2003;30:37-45.
46. Nagori B, Renu S. Role of medicinal plants
in wound healing. Res J Med Plant
2011;5(4):392-405.
47. Thomson PD. Immunology, microbiology,
and the recalcitrant wound. Ostomy Wound
Manage 2000;46:77S-82S; quiz 83S-84S.
48. Pierce GF. Inflammation in nonhealing
diabetic wounds: the space-time continuum
does matter. Am J Pathol 2001;159:399-403.
49. Della Loggia R, Tubaro A, Sosa S, Becker H,
Saar S, Isaac O. The role of triterpenoids in
the topical anti-inflammatory activity of
Calendula officinalis flowers. Planta Med
1994;60:516-520.
50. Rijswik L, Harding K, Bacilious N. Issues
and clinical implications Ostomy Wound
Manage 2000;46:11.
51. Faoagali J. Use of antiseptics in managing
difficult wounds. Primary Intent
1999;7:156–160.
52. Sriwanthana B, P. C, Chompuk L. Effect of
Clinacanthus nutans on human cell-
mediated immune response in vitro. Thai J
Pharm Sci 1996;20:261-267.
53. Yeoh S. The influence of iron and free
radicals on chronic leg ulceration. . Primary
Intent 2000;8:47–55.
54. Politis C, Schoenaers J, Jacobs R, Agbaje JO.
Wound Healing Problems in the Mouth.
Front Physiol 2016;7:507.
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 53 – 58
53
Endokarditis Bakterialis pada Anak : Suatu Tinjauan Untuk Dokter Gigi
(Studi Pustaka)
Sri Ratna Laksmiastuti
Staf Pengajar Bagian Ilmu Kedokteran Gigi Anak Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti
ABSTRACT
Background : Bacterial endocarditis is one of cardiac disorders which is closely related to dentistry.
Infective endocarditis is a serious infection associated with significant morbidity and mortality. It
remains a serious issue in early age. Approximately 10% of the cases are with children below the age
of 10. Tooth extraction, surgery, gingival trauma, scalling, or focal infection on other regions in
children with predelection factor will induce the risk of bacterial endocarditis. The risk of systemic
complication can occur in suscebtible patient. For the susceptible patient, the risk includes serious
sistemic complications. Purpose: A dentist should know the dental management of pediatric dental
patient with cardiac disorders risk. Reviews: Bacterial endocarditis is an bacterial infection
characterized by inflamation or infection of the inner surface of heart (endocardium). Infective
endocarditis is an uncommon but potentially life-threatening infection of the inner heart that is
presumed to be associated with dental procedure that compromise mucosal integrity and lead to
transient bacteremia. Conclusion : A dentist should be capable to identify the patient with the history
of heart disease, to take the history of illness properly, to perform clinical examination, to
communicate with other colleagues, to establish the diagnosis, and perform treatment plan.
Keywords : bacterial endocarditis, children, dentist
PENDAHULUAN
Bakteremia sering kali merupakan bagian
dari kehidupan kita sehari-hari. Pada tubuh kita,
bakteri hidup secara normal di kulit, rongga
mulut, saluran pencernaan, dimana dapat masuk
ke pembuluh darah melalui luka pada kulit.
Bakteri dapat pula masuk ke pembuluh darah
pada saat kita melakukan aktifitas sehari-hari
seperti menggosok gigi dan mengunyah. Rongga
mulut secara umum merupakan tempat
akumulasi bakteri. Oral hygiene yang baik dapat
menurunkan risiko terjadinya bakteremia yang
dapat menyebabkan terjadinya endokarditis.1
Endokarditis bakterialis merupakan salah
satu jenis kelainan pada jantung yang erat
kaitannya dengan bidang kedokteran gigi. Infeksi
endokarditis (IE) adalah salah satu infeksi paling
serius pada manusia dan merupakan penyakit
yang mengancam jiwa. IE adalah infeksi
mikroba pada endokardium (lapisan dalam otot
jantung), dan biasanya melibatkan katup jantung.
Secara umum, terjadinya endokarditis bakterialis
adalah sekitar 0,5 % dari seluruh penyakit
jantung pada anak.2-4 Di negara berkembang,
kejadian pada anak-anak bervariasi antara 0,8-
3,3 / 1000 di rumah sakit umum, dan 20-56 /
1000 pada pusat jantung. Di negara maju,
menunjukkan bahwa terjadi sekitar 1500 kasus
IE per tahun. Penyakit ini lebih sering terjadi
pada pria, dengan rasio pria dan wanita adalah 2 :
1. Selain itu, IE tetap menjadi masalah serius
pada usia dini. Sekitar 10% dari semua kasus IE
terjadi pada anak-anak di bawah usia 10.4,5
Menurut American Heart Association, infeksi
endokarditis merupakan keadaan yang tidak
lazim, tetapi angka kejadiannya tidak jarang.
Penyakit ini terjadi pada 10.000-20.000
penduduk Amerika setiap tahunnya.1,6,7
Pada manajemen pasien, perlu dilakukan
prosedur pencegahan yang tepat, misalnya
penderita telah diberi terapi anti mikroba, dan
pada penderita yang susceptible, penyakit ini
dapat menyebabkan komplikasi serius seperti
stroke, operasi jantung terbuka, bahkan
kematian.1,8
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka
seorang dokter gigi perlu memiliki pengetahuan
yang cukup tentang penyakit ini pada anak,
terutama dalam kaitannya dengan perawatan di
bidang kedokteran gigi. Pengetahuan yang
diperlukan meliputi identifikasi penderita,
anamnesis yang adekuat, penegakkan diagnosis
dan rencana perawatan, serta berkonsultasi
dengan sejawat ahli.
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 53 – 58
54
TINJAUAN PUSTAKA
Definisi dan etiologi
Penyakit jantung dibagi menjadi 2 tipe
secara umum, yaitu : kongenital / bawaan dan
acquired/ didapat. Penyakit Jantung Bawaan
(PJB) terdiri dari PJB Acyanotic dan PJB
Cyanotic. Penyakit jantung yang didapat adalah
demam rematik dan infeksi endokarditis (IE).9
Endokarditis bakterialis adalah infeksi
kuman yang menyerang katub jantung ,
endokardium dan epitel pembuluh darah yang
disebabkan oleh kuman dan beberapa penyakit.2,5
Infeksi endokarditis merupakan infeksi mikroba
yang menyerang permukaan endotelium dari
jantung atau katub jantung yang pada umumnya
terjadi pada pasien dengan kelainan jantung
bawaan ataupun acquired. Infeksi endokarditis
terjadi pada lapisan jantung yang lebih dalam
(endokardium) atau katub jantung. Infeksi ini
dapat menyebabkan kerusakan pada katub
jantung. Endokarditis bakterialis ditandai dengan
inflamasi dan infeksi pada permukaan jantung
yang lebih dalam (endokardium)1,3 Infeksi ini
dapat menyerang semua golongan usia (bayi,
anak, maupun dewasa), baik yang menderita
congenital heart desease maupun pasien tanpa
kelainan jantung.1,3,10
Jamur, chlamydia, rickettsia, dan lain-lain
dapat pula menyebabkan endokarditis ini. Tetapi
penyebab paling umum dari endokarditis adalah
bakteri, dan didiagnosis sebagai endokarditis
bakterialis.11
Kuman penyebab yang sering ditemukan
pada biakan darah dengan frekuensi tinggi adalah
Streptococcus viridans (50-60%), Streptococcus
anhemolyticus (5-10%), Staphylococcus aureus
(10-20%), serta jamur (10%). Pada suatu
penelitian yang dilakukan pada sebelas kultur
darah penderita yang positif terdiagnosis
endokarditis, Streptococcus viridians didapatkan
sebanyak empat kasus, dan Staphylococcus
aureus tiga kasus.12
Bakterimia transien umumnya terjadi
setelah trauma pada mukosa karena dental
procedures. Streptococus adalah etiologi utama
infeksi endokarditis. Sekitar 40% dari kasus
endokarditis menunjukan kultur positif adanya
Streptococcus yang berasal dari rongga mulut .
Maka dari itu, banyak ahli berpendapat bahwa
penyebab utama infeksi endokarditis adalah
prosedur perawatan gigi.13
Seperti telah tersebut di atas, diantara
variasi jenis-jenis bakteri , penyebab utama
endokarditis adalah streptococcus viridans, yang
merupakan penyebab dari sub akut endokarditis.
Streptococcus viridans merupakan jumlah
terbanyak pada kelompok streptococcus, dan
merupakan bakteri komensal utama di rongga
mulut.
Actinobacillus actinomycetemcomitans
dilaporkan juga merupakan salah satu agen
penyebab. Sedangkan porphyromonas gingivalis,
yang merupakan agen penyebab utama
periodontitis pada orang dewasa, tidak
ditemukan pada biakan darah pasien endokarditis
bakterialis.11
Patogenesis
Endocarditis bacterialis merupakan akibat
dari interaksi yang kompleks dari beberapa
faktor seperti endotelium, bakteri dan respon
imun dari host.3 Infeksi endokarditis terjadi bila
bakteri di pembuluh darah memasuki katup
jantung yang tidak normal atau jaringan jantung
yang lain. Beberapa tindakan pada prosedur
perawatan gigi dapat menyebabkan bakterimia.
Bakteri memasuki pembuluh darah selama
prosedur perawatan gigi, menuju jantung dan
dapat tinggal di katup jantung yang mengalami
kelainan. Bakteri berkembang dan menyebabkan
terjadinya infeksi yang menjalar ke otak, paru,
ginjal atau pun limpa.14 Tindakan medis yang
invasif dapat juga menyebabkan bakteremia bila
luka terjadi pada daerah yang umum ditinggali
oleh bakteri normal.1
Tiga komponen utama harus berinteraksi
untuk menghasilkan IE: 1) lesi jantung yang
mendasari dan kerusakan endokardial, 2)
keadaan yang mengarah ke lesi signifikan
mukosa, yang rentan terhadap bakteremia, dan 3)
volume inokulum mikroba dan virulensi dari
agen bakteri.15
Menurut American Heart Asssociation
(AHA), secara umum bakteri masuk ke tubuh
setelah tindakan di bidang kedokteran gigi,
tonsilektomi atau adenoidectomy, pemasangan
rigid bronchoscope, pembedahan pada saluran
nafas, saluran pencernaan, saluran kencing,
gallbladder, dan prostat.6
Pencegahan dan Penatalaksanaan di Bidang
Kedokteran Gigi
Pedoman tentang pencegahan endokarditis
bakterialis pada anak di bidang kedokteran gigi
selalu berkembang, diperbarui dan
disederhanakan dengan perhatian utama pada
pasien yang mempunyai resiko besar terhadap
penyakit dan kematian akibat penyakit ini.
Dewasa ini profilaksis lebih fokus
direkomendasikan pada pasien dengan
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 53 – 58
55
prosthetic heart valve, pasien dengan riwayat
infeksi endokarditis, pasien dengan penyakit
jantung bawaan, dan pasien paska transplantasi
jantung.16 American Heart Association
merekomendasikan pemberian profilaksis
antiobiotik untuk mencegah terjadinya
endokarditis bakterialis. Tetapi masih terdapat
keraguan tentang pemberian antibiotika
profilaksis pada pasien anak dengan oral hygiene
yang baik.17
Profilaksis berupa terapi antibakterial
direkomendasikan pada tindakan perawatan yang
diperkirakan terjadi bakterimia yang melibatkan
organisme penyebab bakterialis endokarditis.
Tindakan tersebut salah satu contohnya adalah
ekstraksi gigi. Ampisilin telah direkomendasikan
sebagai obat profilaksis bakterialis endokarditis
untuk anak yang menjalani perawatan di rongga
mulut, dan saluran nafas. Pada pasien dengan
alergi penisilin obat dapat diganti dengan
cephalosporin, clindamycin, azithrocyn atau
clarithromycin.18
Pemberian resep antibiotika dapat
dilakukan oleh dokter gigi, dokter spesialis anak,
ataupun dokter spesialis jantung.19 Secara
umum, perawatan di bidang kedokteran gigi
yang beresiko terjadinya endokarditis bakterialis
adalah ekstraksi gigi, tindakan periodontal
(scaling, root planning, probing, dan perawatan),
dental implant, reimplant gigi avulsi, perawatan
endodontik, subgingival placement of antibiotic
fibers or strips, pemasangan band orthodontic,
anestesi intraligamen, prophylactis cleaning of
teeth or implant, dan perawatan bidang
kedokteran gigi yang lain dimana terdapat
kemungkinan terjadi perdarahan.20-21 Kebiasaan
menjaga oral hygiene yang baik pada anak,
merupakan tahap penting dalam pencegahan
bakterialis endokarditis. Pemeriksaan rutin ke
dokter gigi sangat diperlukan. Pemeliharaan oral
hygiene yang baik dan tepat sangat penting,
termasuk di dalamnya menyikat gigi dan
flossing.6
Tindakan di bidang kedokteran gigi yang
dapat menyebabkan terjadinya bakteremia
transien, dan perlu atau tidaknya profilaksis
endocarditis, dituliskan pada tabel 1.
Tabel 1. Profilaksis endocarditis untuk prosedur
dental.9,23,24
Profilaksis
direkomendasikan
Profilaksis tidak
direkomedasikan
Ekstraksi gigi
Tindakan Periodontal
(pembedahan, skeling,
root planing, probing
dan recal maintenance)
Pemasangan implan dan
reimplatasi gigi yang
avulsi.
Instrumentasi
Endodontik atau bedah
pada daerah apeks
Pemasangan
Subgingival antibiotics
fibers or strips
Pemasangan awal
orthodontic bands
Intraligamentary local
anesthetic infections
Prophylactic cleaning
of teeth or implants,
where bleeding is
anticipated
Insisi dan drainase atau
prosedur lain yang
melibatkan jaringan
yang terinfeksi
Injeksi rutin anestesi
pada jaringan yang tidak
terinfeksi
Tindakan radiografi
dental
Pemasangan atau
pelapasan piranti
ortodontik atau
prostodontik
Aktivasi piranti
ortodontik
Sheeding of primary teeth
Pemasangan rubber dams
Pemasangan rubber dams
Post operative suture
removal
Taking oral impressions
Aplikasi fluoride
American Heart Association
menyampaikan rekomendasi tentang penggunaan
antibiotic pencegahan infeksi endocarditis
bakterialis untuk meminimalkan risiko
resistensi pada obat. Rekomendasi tercantum
pada tabel 2.1
Anak-anak yang sebelumnya telah
mengkonsumsi antibiotik jangka panjang, harus
diberi resep obat alternatif sesuai protokol untuk
menghindari perkembangan organisme oral yang
resisten. Obat kumur antiseptik oral pra operasi,
seperti chlorhexidine gluconate 0,2%,
direkomendasikan untuk mengurangi bakteri
mulut. Teknik manajemen perilaku pada anak,
dalam hal ini bermanfaat. Analgesia nitrous
oxide-oxygen sedasi sadar telah terbukti
bermanfaat dalam mengurangi kecemasan pada
pasien anak. Jika sedasi sadar digunakan, tanda
vital dan saturasi oksigen selama prosedur harus
dimonitor secara hati-hati, dan peralatan
resusitasi kardio-pulmoner harus siap pakai.9,25,26
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 53 – 58
56
Tabel 2. Rekomendasi prosedur pemberian obat.9,25
Regimen : Dosis tunggal 30-60 menit sebelum
tindakan
Situasi Obat Dewasa
Anak
Oral Amoxicillin 2 g 50
mg/k
g
Pasien tidak
dapat
mengkonsum
si obat lewat
mulut
Ampicillin 2 g IM
or IV
50
mg/k
g IM
or IV
Cefazoin/ceftria
xone
1 g IM
or IV
50
mg/k
g IM
or IV
Pasien alergi
penicillin
Cephalexin 2 g 50
mg/k
g
Clindamycin 600 mg
20
mg/k
g
Azithromycin
/clarithromycin
500 mg 15
mg/k
g
Pasien alergi
penicillin
dan tidak
dapat
mengkonsum
si obat lewat
mulut
Cefazolin 1 g IM
or IV
50
mg/k
g IM
or IV
Cefriaxzone
/clindamycin
600 mg
IM or
IV
20
mg
IM or
IV
Penilaian pra operasi menyeluruh terhadap
obat reguler anak (termasuk antikoagulan,
antiaritmia, dan antihipertensi) sangat penting
untuk menghindari interaksi obat yang potensial
selama pengobatan. Tidak ada kontraindikasi
untuk penggunaan vasokonstriktor dalam larutan
anestesi lokal. Hindari penggunaan bedah
elektro, electric pulp test, dan pembersih
ultrasonik pada anak-anak dengan pacu jantung.
Pulpotomi dan pulpektomi merupakan
kontraindikasi pada anak-anak ini karena
kemungkinan terjadi bakteremia kronis
berikutnya. Jika anestesi umum diindikasikan,
prosedur perawatan gigi harus dilakukan di
rumah sakit, di mana tersedia perawatan suportif
yang memadai tersedia.9,26
Diskusi
Sebagian besar kelainan jantung pada anak
adalah kongenital, dengan prevalensi 8 pada tiap
1000 kelahiran hidup. Bakterialis endokarditis
bersama dengan myocarditis selain dapat
menyebabkan kematian, juga menyebabkan
ketidakmampuan pada pasien.27 Bakterialis
endokarditis merupakan suatu infeksi yang
mengancam kehidupan seseorang, dengan
tingkat kematian mencapai 30% walaupun telah
diberi pengobatan antibiotika. Bahkan menurut
American Heart Association tingkat kematian
yang diakibatkan penyakit ini mencapai 40%.
Mikroorganisme penyebab, masuk ke aliran
darah melalui beberapa pintu masuk, terutama
permukaan mukosa. Gingiva dan ligamen
periodontal merupakan salah satu titik penting
pintu masuknya bakteri ke aliran darah. Bahkan
aktifitas menggosok gigi yang dilakukan rutin
setiap hari dapat pula menyebabkan
bakteremia.27 Peningkatan insiden terjadinya
endokarditis bakterialis dipengaruhi oleh banyak
faktor, yaitu peningkatan survival rate anak
dengan congenital heart desease, peningkatan
penggunaan kateter central venous jangka
panjang, peningkatan pemakaian bahan
prosthetic dan katup. Pasien anak yang tidak
mempunyai riwayat kelainan jantung, tetapi
mempunyai resiko terkena endokarditis
bakterialis adalah anak-anak dengan defisiensi
sistem imun; seiring dengan meningkatnya
survival rate pada anak-anak ini , peningkatan
pemberian obat-obatan intravena, serta
peningkatan penggunaan jangka panjang alat
penunjang kehidupan pada bayi baru lahir
dengan sakit yang berat.28
Bakteremia transien (sementara) dapat
juga ditemukan pada anak yang normal,
misalnya pada pencabutan gigi, operasi, luka
pada gingiva, scaling, atau infeksi fokal di
tempat lain, bahkan menggosok gigi. Tetapi pada
anak normal hal tersebut hampir tidak pernah
menyebabkan endokarditis bakterialis. Diduga,
permukaan endokardium yang tidak normal atau
pun katub yang cacat merupakan tempat
predeleksi.29
Bakteremia dapat terjadi akibat beberapa
macam tindakan medis. Pencabutan gigi
merupakan tindakan medis dengan resiko
terjadinya bakteremia sebesar 40-100% dengan
organisme penyebab Streptococcus viridans. Bila
dibandingkan dengan tindakan medis yang lain
(endoskopi, kolonoskopi, barium enema, reseksi
trans uretra pada prostat, transechopageal
echocardiography) mempunyai resiko paling
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 53 – 58
57
tinggi terhadap kemungkinan terjadinya
bakterialis endokarditis.30
Pada penelitian yang dilakukan oleh
Sivam dkk, tentang prevalensi dan intensitas
bakteremia bila dihubungkan dengan perawatan
orthodonsi, menunjukan pada hasil awal terdapat
peningkatan yang signifikan terjadinya
bakteremia pada saat pemasangan separator.
Sedangkan potensi perkembangan bakterialis
endokarditis sangat rendah, sehingga pemberian
antibiotika profilaksis masih menjadi
pertimbangan.8 Pemakaian obat kumur
antiseptik seperti 0,2% chlorhexidine gluconate
perlu dilakukan sebelum perawatan. Resistensi
pasien terhadap antibiotika perlu mendapat
perhatian, terutama pada pasien yang baru saja
mendapat terapi antibiotika jangka panjang.
Perawatan pulpotomi kontra indikasi dilakukan
pada pasien dengan resiko bakterialis
endokarditis, sedangkan penggunaan
vasokonstriksi tidak kontraindikasi pada pasien,
sepanjang dilakukan aspirasi suntuk mencegah
terjadinya injeksi intravena. Pemeliharaan oral
hygiene yang baik, memegang peranan penting
untuk menurunkan resiko terjadinya bakterialis
endokarditis. Pendidikan berkelanjutan pada
tenaga kesehatan termasuk dokter gigi penting
untuk dilakukan, sebagai panduan protokol
terhadap pasien.31,32
DAFTAR PUSTAKA
1. Cabell CH, Abrutyn E, Karchmer AW.
Bacterial endocarditis : the desease,
treatment, and prevention. Circulation.
American Heart Association. 2003; 107: 185-
7.
2. Casamassimo PS, Fields HW, McTigue DJ,
Nowak AJ. Pediatric dentistry through
adolescence. 5th ed. St. Louis-Missouri :
Elsevier Saunders; 2013.p.122-4.
3. Seymour RA, Lowry J, Whitworth JM et al.
Infective endocarditis, dentistry and antibiotic
prophylaxis : time for a rethink? British Dent
J. 2000; 189 (11): 610-5.
4. Rahayuningsih SE, Kuswiyanto RB,
Situmorang HE et al. Infective endocarditis
in a β-thalasemia major child. Cardiovasc J.
2015; 7(2): 145-9.
5. Marinov L, Shivachev P. Infective
endocardiitis in children-clinical and outcome
evolution. J of IMAB. 2009; 1: 13-5.
6. Heart disease bacterial endocarditis.
Cincinnati Children’s Hospital Medical
Center. Available from
http://www.cincinnatichildrens.org/health/hea
rt-encyclopedia/disease. Diakses tanggal 18
Januari , 2019.
7. Hay WW, Hayward AR, Levin MJ, et al.
Current pediatric diagnosis & treatment. Ed.
Ke-15. International Edition. New York : Mc
Graw Hill; 2001.h.519.
8. Sivam R. Infective endocarditis prophylaxis
in orthodontics : a literature review. Saudi
Dent J. 2002(14); 93-8.
9. Premkumar S. Manual of pediatric dentistry.
1st ed. New Delhi : Jaypee Brothers Medical
Publishers; 2014: 570-5.
10. Little JW, Falace DA, Miller CS ,Rhodus NL
.Dental management of the medically
compromised patient. 7th ed. Missouri :
Mosby Elsevier Company ; 2008. h. 18.
11. Ito HO. Infective endocarditis and dental
procedures : evidence,pathogenesis, and
prevention. J of Med Investigation. 2006; 53.
12. Zacherl S, Feyertag C, Mukhar US, Wimmer
M. Bacterial endocarditis in childhood.
Microbiology Research. Available from
http://www.microbugs.org/ . Diakses tanggal
14 Januaril, 2019
13. Roberts G, Davies R, Fulford M, Longman L.
A dental care standard for patient at risk of
infective endocarditis (IE). Available from
http://www.rcseng.ac.uk/fds/publications-
clinical-guidelines. Diakses tanggal 15
Januari, 2019.
14. Infectious Endocarditis. U.S. National Library
of Medicine. Available from
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus.html.
Diakses tanggal 16 Januari, 2019.
15. Di Filippo S. Prophylaxis of infective
endocarditis in patient with congenital heart
disease in the context of recent modified
guidelines. Archives of Cardiovascular
Disease. Elsevier Masson; 2012: 454-460.
16. Kim A, Keys T. Infective endocarditis
prophylaxis before dental procedures : new
guidelines spark controversy. Cleveland
Clinic J of Med. 2008 (75); 89-92.
17. Soxman JA. Subacute bacterial endocardiitis :
considerations for the pediatric patient. J am
Dent Assoc. 2000 (131) ; 668-9.
18. Capitano B, Quintiliani R, Nightingale CH,
Nicolau DP. Antibacterials for peophylaxis
and treatment of bacterial endocarditis in
children. PubMed U.S National Library of
Medicine. Available from
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ .
Diakses tanggal 14 Januari, 2019.
19. Heart condition in children-bacterial
endocarditis. University of Rochester Medical
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 53 – 58
58
Center. Available from
http://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/
content.cfm. Diakses tanggal 14 Januari,
2019.
20. American Heart Association Guidelines :
Bactaerial Endocarditis Prophylaxis. J Am
Coll Cardiol. 2008 (52); 676-685.
21. Abdallah H. What is bacterial endocarditis.
The Children’s Heart Institute. Available
from
http://childrensheartinstitute.org/educate/bact
endo/bactendo.htm. Diakses tanggal 16
Januari, 2019.
22. Silvestry FE, Glick M, Tarka EA, Herling IM.
Disease of the cardiovascular system. Dalam
Burket’s Oral Medicine Diagnosis &
Treatment. Martin S Greenberg, Michael
Glick (editor). Ed.Ke-10. Ontario : BC
Decker; 2003.h.363.
23. Casamassimo PS, Fields HW, McTigue DJ,
Nowak AJ. Pediatric dentistry through
adolescence. 5th ed. St. Louis-Missouri :
Elsevier Saunders; 2013.p.122-4.
24. Seymour RA, Lowry J, Whitworth JM et al.
Infective endocarditis, dentistry and antibiotic
prophylaxis : time for a rethink? British Dent
J. 2000; 189 (11): 610-5.
25. Weddell JA, Sanders BJ, Jones JE. Dental
problems of children with special health care
needs. In Dentistry for The Child and
Adolescent. Jeffrey A Dean (editor). 10th ed.
St Louis- Missouri : Elsevier; 2016.p.535-8.
26. Cameron AC, Widmer RP. Handbook of
pediatric dentistry. 3rd ed. Sydney : Mosby
Elsevier Company; 2008.p.
27. Koch G, Poulsen S. Pediatric dentistry a
clinical approach, Ed.Ke-2. United Kingdom :
Blackwell Publishing; 2009.h.319.
28. Hay WW, Hayward AR, Levin MJ, et al.
Current pediatric diagnosis & treatment. Ed.
Ke-15. International Edition. New York : Mc
Graw Hill; 2001.h.519.
29. Hay WW, Hayward AR, Levin MJ, et al.
Current pediatric diagnosis & treatment.
Ed.Ke-15. International Edition. New York :
Mc Graw Hill; 2001.h.519.
30. Wilson W, Taubert KA, Gewitz M et al.
Prevention of infective endocarditis.
Guidelines from American Heart Association.
Circulation. 2007; 116: 1736-1754.
31. Rushani D, Kaufman JS, Ittu RI et al.
Infective endocarditis in children with
congenital heart disease. Cumulative
incidence and predictors. J of American Heart
Association. Circulation. 2013;: 1412-9.
32. Marwah N. Textbook of pediatric dentistry.
3rd ed. New Delhi; Jaypee Brothers Medical
Pub; 2014.p.853.
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 59 – 65
59
Infeksi pada Dental Implan Serta Perawatannya
(Studi Pustaka)
Trijani Suwandi
Staf Pengajar Bagian Periodonti Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti,
ABSTRACT
Background: Implant treatment has a high success rates and stability, but failure can occur,
an in fact it is hard to know the causes of such failure. Objective: This article reviews
infection in dental implants, risk factor for dental implant, classified according to the
treatment phase : infection prior to the implant, peri-surgical infection, severe post-syrgical
infection, peri-implant disease. Literatur review: Difficulties can arise in any area of
biological function, however implant dentistry has been fraught with compromises and
complication. Hence, it is mandatory for every clinician to know, how and why the failures
occur and how best we can prevent then in order to give the upcoming branch of dentistry a
new horizon. Conclusion: Early detection and treatment of early progressive bone loss
around dental implants by mechanical debridement, antimicrobial therapy and regenerative
therapy.
Keywords : dental implant infection, implant failure, risk factor, treatment
PENDAHULUAN
Dunia kedokteran gigi telah mengalami
banyak perubahan selama seperempat abad
terakhir, khususnya kedokteran gigi implant.
Saat ini terjadi peningkatan jumlah pasien untuk
melakukan pemasangan implan dan dokter gigi
dihadapkan pada pilihan perawatan yang
semakin komplek. Meskipun tingkat kesuksesan
implan dilaporkan tinggi, akan tetapi banyak
kegagalan terjadi. Karenanya pengetahuan
menyeluruh mengenai berbagai aspek penyebab
kegagalan sangat diperlukan, baik dalam
pemilihan kasus, prosedur bedah dan prostetik
yang ideal.1
Studi klinis longitudinal melaporkan
tingkat kesuksesan 10 tahun adalah 81-85%
pada maksila dan 98-99% pada anterior
mandibula2 akan tetapi Esposito dkk. melaporkan
kegagalan implan berhubungan dengan faktor
biologis yang ditemukan pada 2812 sampel
implan dan ditemukan tingkat kegagalan 7,7% di
atas periode 5 th.3
Menurut Albrektsson dkk. kriteria
kesuksesan implan adalah implan secara klnis
tidak goyang, pada radiografis tidak ditemukan
peri-implan radiolusensi, kehilangan tulang
vertikal kurang 0,2 mm setiap tahun setelah
pemakaian satu tahun, tidak ada tanda persisten
dan irreversible dan gejala sakit, infeksi,
parestesia, tingkat kesuksesan 85% pada akhir 5
tahun observasi dan 80% pada akhir masa 10
tahun untuk kriteria kesuksesan minimal.4
Menurut The American Academy of
Periodontology 2000 kriteria kesuksesan adalah
tidak ada tanda persisten atau gejala sakit infeksi,
neuropati, parestesia dan menganggu struktur
vital, tidak ada mobilitas implan, tidak ada
radiolusensi peri-implan kontinu, dapat terjadi
kehilangan tulang progresif (kurang dari 0,2 mm
tiap tahun) setelah remodeling fisiologis selama
1 tahun berfungsi.5
Tingkat kesuksesan kumulatif dental
implan telah dievaluasi dalam jangka pendek (<
5 tahun), menengah (5-10 tahun) dan jangka
panjang (>10 tahun), dan dipengaruhi oleh
faktor-faktor lokasi implan, posisi rahang, tipe
implan, diameter implan, panjang implan,
konstruksi prostetik, jumlah gigi yang
digantikan.1
TUNJAUAN PUSTAKA
Faktor Resiko Dental Implan
Faktor resiko dental implan terbagi dalam
: faktor resiko terkait dokter gigi, implan dan
host. Faktor resiko terkait dokter gigi meliputi
faktor sebelum, selama dan paska bedah. Faktor
sebelum bedah seperti penggunaan radiografis
untuk evaluasi diagnostiK kualitas dan kuantitas
tulang termasuk periapikal, panoramik,
computed tomography dan magnetic resonance
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 59 – 65
60
imaging. Radiografi periapikal terdapat
pembesaran 14% dan panoramik dengan
pembesaran 25%. Hal ini dapat menyebabkan
kesalahan dalam perencanaan dan kinerja
implan, sehingga perlu membuat metode khusus
untuk merekam pengukuran anatomi yang tepat.6
Pemanasan dari friksi peralatan dengan torsi
yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan
implant bed. Sekitar 3,6% kegagalan implan
berhubungan dengan trauma bedah. Faktor lain
adalah penempatan implan yang tidak ideal
sehingga menyebabkan pembebanan non-axial
selama mastikasi, peningkatan resiko dari
fraktur implan dan fraktur tulang peri-implan
biasa terjadi pada regio posterior pada pasien
dengan kepadatan tulang rendah.6
Desain mahkota yang tidak tepat
berkontribusi terhadap kegagalan. Cusp terlalu
tinggi dan alignment oklusal yang terlalu tinggi
dapat meningkatkan tekanan oklusal sampai pada
tingkat yang tidak dapat diterima. Lebar
mahkota, tinggi cusp, guidance dan alignment
oklusal dapat digunakan untuk mengontrol
tekanan oklusal.7
Material dental implan dan karakteristik
permukaan serta relasi posisi implan
berpengaruh terhadap keberhasilan implan.
Material implan ideal sebaiknya biokompatibel,
kekakuan yang tepat untuk fungsi prostetik,
dapat beradaptasi dengan baik pada tulang dan
gingiva, resisten terhadap mikroba peri-implan.
Penggunaan material implan yang tidak
biokompatibel menyebabkan kegagalan implant
yang diinisiasi respon host yang merugikan.8
Coating permukaan implan dengan titanium
oxide (TiO2), ceramic coating atau diamond
coating. Umumnya material dental implan yang
digunakan biokompatibel seperti titanium,
titanium–aluminium-vanadium (Ti-6Al 4V),
cobalt-chromium-molybdenum, dan jarang
menggunakan alloy.9
Insiden kegagalan karena posisi implan
diestimasi 10%. Kegagalan tersebut dapat
dihindari dengan rencana perawatan yang tepat,
penggunaan surgical guide dan penguasaan
restoratif yang baik. Malposisi implan
menyebabkan masalah biomekanikal pada
sambungan screw atau pada implan itu sendiri
yang menyebabkan tekanan yang besar.10
Faktor host dibagi menjadi faktor resiko
lokal dan sistemik. Faktor resiko lokal terdiri dari
kualitas dan kuantitas tulang, tulang iradiasi,
tekanan oklusal biomekanik. Pasien dengan
kuantitas dan kepadatan tulang rendah
mempunyai resiko kegagalan. Jaffin dan Berman
pada analisis 5 tahun melaporkan bahwa 35%
dari keseluruhan implan gagal pada tipe tulang
kelas IV dengan kortek yang tipis, kekuatan
modular buruk, dan kepadatan trabecular
rendah. Osteoporosis sistemik merupakan faktor
resiko yang menyebakan kegagalan
osseointegrasi.11
Efek samping dari radiasi berupa
osteoradionecrosis. Meskipun terapi radiasi
bukan menjadi kontra indikasi absolut pada
perawatan implan, tetapi Jacobsson dkk
menunjukkan peningkatan hilangnya implan
pada waktu yang lama. Restorasi dental implant
yang optimal tetap dapat menyebabkab
kehilangan tulang peri-implan, karena implan
gigi tidak memiliki reseptor stress yang berada
dalam ligamentum periodontal dan sistem
stomatognatik kurang peka dibandingkan gigi
yang sehat. Beban diterima langsung oleh
jaringan keras implant karena implan tidak
terlindungi oleh ligamentum periodontal.12
Klasifikasi Infeksi Peri-Implan
Quirynen membagi dalam empat
klasifikasi infeksi : 1). infeksi sebelum implan
2). infeksi saat bedah, 3). infeksi paska bedah
dan 4). penyakit peri-implan.13
Klasifikasi 1 : infeksi sebelum implan
Pada keadaan septik aktif sebaiknya
dikontraindikasikan untuk penempatan implant
karena kemungkinan terjadi septik emboli yang
menyebabkan infeksi segera maupun lanjut
sesudah bedah (osteomyelitis, peri-implant
abscess). Hal ini disebabkan adanya sisa-sisa
epitel yang membahayakan osseointegrasi.
Daerah infeksi tersebut harus dilakukakan
dekontaminasi secara sempurna supaya
didapatkan daerah implant yang steril.14
Perawatan dapat digunakan laser Er:Yag
atau laser diode yang efektif dalam daerah
infeksi.15 Pasien dengan riwayat penyakit
periodontal dapat mengontaminasi implan dalam
mulut. Studi Ellegard menunjukkan bahwa
pasien dengan riwayat penyakit periodontal
dengan kerusakan tulang yang besar dapat
berhasil dilakukan perawatan implan dan dapat
mencapai osseointegrasi16, akan tetapi Karoussis
menunjukkan bahwa pasien yang menggunakan
implan karena hilangnya gigi disebabkan oleh
periodontitis mempunyai rate survival rendah
dan komplikasi besar dibanding pasien
kehilangan gigi karena penyebab yang lain.17
Hasil konsensus implantologi
menyimpulkan bahwa pasien dengan penyakit
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 59 – 65
61
periodontal mempunyai tingkat keberhasilan
implan rata-rata 91-92 % dan pasien tanpa
penyakit periodontal mempunyai tingkat
keberhasilan 97%.18 Akan tetapi insidensi peri-
implantitis dan kerusakan tulang marginal
meningkat secara signifikan pada pasien dengan
penyakit periodontal. Subyek dengan resiko
periodontits mempunyai kegagalan implan lebih
tinggi.19
Pertimbangan khusus perawatan implan
pada pasien penyakit periodontal antara lain :
Resorpsi progresif pada edentulous maksila
mempunyai hubungan langsung dengan
prognosis implan dan tinggi tulang yang tersisa.
Gigi dengan prognosis buruk yang tidak
mendapatkan perawatan teratur sebaiknya
dilakukan ekstraksi dan memerlukan perawatan
pendahuluan untuk mengatasi penyakit
periodontal.20
Klasifikasi 2 : infeksi saat bedah.
Bedah intraoral secara tradisional
diklasifikasikan sebagai bedah yang bersih
kontaminasi atau bedah kontaminasi, tergantung
ketika intervensi dilakukan. Daerah bedah dapat
terkontaminasi melalui banyak sebab dan bakteri
dapat berpenetrasi pada lapangan kerja, akan
tetapi vaskularisasi yang sempurna pada daerah
kerja dan tidak adanya infeksi terdahulu dapat
mencegah proses infeksi yang terjadi selama
intervensi. Sumber kontaminasi bedah sebagian
besar berasal dari instrument sendiri (udara,
aspirasi, instrumen) dan adanya saliva pada
daerah bedah dan berhubungan dengan muka dan
bibir.13
Banyak tehnik yang digunakan untuk
mencegah hal ini seperti mengurangi sekresi
saliva dengan atropine, double aspirasi untuk
mencegah kontaminasi saliva pada bedah, dan
penggunaan kumur klorheksidin untuk
mengurangi jumlah bakteri dalam rongga
mulut.21 Manifestasi klinik infeksi disebabkan
dari kontaminasi peri-operatif biasanya dalam
bentuk abses peri-implan, yang ditandai
radiolusensi peri apikal pada X-ray, yang sering
menjadi fistula.13
Klasifikasi 3 : Infeksi paska bedah
Komplikasi infeksi pada bedah implan
dapat terjadi karena virulensi bakteri dapat
menyebabkan segala macam infeksi yang dapat
mengancam jiwa. Infeksi oral dan maksilofasial
dapat ditemukan dan perawatan infeksi termasuk
implant dan perawtan bedah yang tepat , serta
dilengkapi antibiotik. Salah satu proses infeksi
sebagian berasal dari bedah bone graft
dihubugkan dengan penempatan implan,
berhubungan dengan reaksi immunologikal.22
Dalam melakukan regerenasi tulang
sebaiknya mengikuti prinsip Gottlow Nyman dkk
antara lain persiapan daerah regenerasi dengan
memelihara vaskularisasi graft dengan baik,
sehingga didapatkan nutrisi yang cukup dan
mencegah nekrosis awal, yang akan
memfasilitasi regenerasi dan proses
penyembuhan luka dan mencegah jaringan
sekitar kolaps bertujuan untuk mempertahankan
ruangan untuk regenerasi. Guided Tissue
Regeneration diaplikasikan untuk mencegah
infiltasi jaringan lunak ke dalam graft. Beberapa
prinsip dasar penggunaan GTR yaitu : imobilitas
material graft, menjaga daerah bersih,
vascularisasi berjalan baik, aman dan
biokompatibel.22
Klasifikasi 4 : Infeksi Peri-implan
Infeksi peri-implan merupakan infeksi di
sekeliling implan, yang ditandai dengan
perdarahan saat probing.23 Penyakit periodontal
dan peri-implan merupakan patologis multifaktor
dengan etiologi utama bakteri. Strain yang
berhubungan dengan onset dan perkembangan
penyakit periodontal juga diidentifikasi pada
jaringan peri-implan yang disebut peri-
implanitis.24 Patogen uatama peri-implantitis
adalah bakteri Gram negatif anaerob, dengan
peningkatan persentasi dari motile rod, fusiformis
dan spricochaeta, bacilli.25
Bakteri yang terbesar Prevotella
intermedia, Fusobacterium nucleatum,
Porphyromonas gingivalis, Capnocytophaga dan
Campylobacter rectus. Bakteri yang jarang
ditemukan Actinobacillus actinomycetem
commitans pada peri-implantitis, yang lebih
banyak berhubungan dengan penyakit
periodontal. Adanya Pg mengindikasikan awal
peri-implantitis atau peri-implan mukositis.
Adanya Pg, Aa atau Pi pada poket peri-implan
mengindikasikan resiko tinggi kemungkinan
hilangnya insersi selama fase lanjut dan pasien
dengan partial edentulous mempunyai resiko
infeksi lebih tinggi daripada pasien dengan
complete edentulous.26
Jenis Penyakit Implan dan Perawatan
A. Peri-implant Mucositis
Reaksi peradangan reversible pada
jaringan lunak di sekeliling implan saat
berfungsi. Secara klinis ditandai dengan :
adanya plak dan kalkulus, udem, kemerahan dan
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 59 – 65
62
hiperplasia gingiva, perdarahan saat probing,
eksudat atau pembentukan pus (gingival mikro
abses). Secara radiografis tidak ditemukan
resorpsi tulang.23,27
B. Peri-implant osteitis (Peri-implantitis)
Reaksi peradangan irreversible pada
jaringan lunak dan keras di sekeliling implan
saat berfungsi, karena terjadi kehilangan tulang
natural. Jika tidak dirawat. pada fase inisial
menunjukkan gejala yang sama dengan peri-
implan mukositis, tapi pada tahap lanjut terjadi
kehilangan tulang. Tanda yang paling sering :
adanya plak bakteri dan kalkulus, edema,
kemerahan jaringan peripheral, hiperplasia
mukosa dengan berkurangnya keratin gingiva,
poket yang dalam, perdarahan dan pembentukan
pus setelah probing dan atau palpasi, kerusakan
tulang vertikal berhubungan dengan poket peri-
implan, radiografis tampak resorpsi tulang,
mobilitas implan, kadang-kadang terasa sakit.23
Kegoyangan implan secara kontinu dan
radiolusensi peri-implan mengindikasikan
penyakit mencapai final, ditandai dengan
kehilangan total tulang. Pemeriksaan radiografis
sangat penting karena meskipun X-ray hanya
menunjukkan tulang mesial dan distal
permukaan implant, defek tulang dengan bentuk
sirkular atau corong dapat menunjukkan
etiologi, perkembangan klinis dan prognosis.
Defek horizontal berjalan lambat.
Kecenderungan mempunya lebih favourable
prognosis karena sering berhubungan dengan
resesi jaringan lunak. Sudut yang terbentuk
dengan permukaan implant lebih dari 60 derajad,
sedangkan defek vertikal berkembang lebih
cepat, karena poket dengan pertumbuhan epitel
di dalam, dan infeksi purulent ketika kedalaman
poket lebih dari 5 mm. Sudut yang dibentuk
dengan permukaan implant kurang dari 60
derajad.27
Jovanovic dan Spiekermann’s klasifikasi
peri-implantitis (1995) yaitu : Peri-implantitis
klas 1 : minimum kerusakan tulang horizontal
dengan slight peri-implan bone loss, Peri-
implantitis klas 2 : kerusakan tulang moderat
dengan kerusakan vertikal soliter, Peri-
implantitis klas 3 : kerusakan tulang horisontal
moderat atau intense dengan extensive
circumferential bone lysis, Peri-implantitis klas 4
: kerusakan tulang horizontal intense dengan
extensive circumferential bone lysis dan
kehilangan tulang lingual atau dinding tulang
vestibular.27
Perawatan
Perawatan peri-implan mucositis
Secara prinsip berfokus pada kontrol plak
bakteri, meskipun perawatan bedah lain dapat
dilakukan untuk eliminasi hiperplasia sekeliling
jaringan lunak. Selanjutnya perawatan terdiri
beberapa fase :1). Profesional peri-implan
hygiene : eliminasi mekanik plak bakteri 54,
Irigasi poket dengan CHX 0,12%. 55,
Pembuangan dan desinfeksi prosthesis,
modifikasi design prosthesis unhygienic, kadang
flap partial thickness dibentuk dengan irigasi
salin, diikuti aplikasi krem tetrasiklin, Perawatan
laser dengan 1,5-2 w diode pada kasus
refractory; 2). Personal peri-implan hygiene: plak
kontrol kemis dengan CHX 0,12% tiap 12 jam;
3). Antibiotik lokal dan sistemik; 4). Regular
professional control.27
Perawatan Peri-implantitis
Persyaratan mendasar perawatan peri-
implantitis yang sukses, dengan atau tanpa
protokol regenerasi tulang yaitu dekontaminasi
permukaan implan dengan membuang bakteri
dan toksin. Perawatan peri-implantitis harus
didasarkan pada stabilisasi kerusakan tulang
progresif, dan kadang diperlukan perawatan
regeneratif.
Perawatan dibagi menjadi 2 fase. Fase 1 :
perawatan konservasi inisial dilakukan dengan
cara metode manual-mekanikal untuk
mengontrol plak bakteri (sama dengan
mucositis), metode kemis : CHX 0,12%, asam
sitrat, lokal aplikasi tetrasiklin, laser diode : 1 W
untuk 20 detik.
Fase 2 merupakan perawatan regeneratif
yang terdiri dari perawatan jaringan lunak dan
perawatan permukaan implan. Insisi crestal
bentuk scallop sekeliling leher impan untuk
mengeliminasi jaringan granulasi dari poket,
kemudian flap mukoperiosteal dibuka untuk
mengeliminasi jaringan granulasi dari defek
tulang dengan kuret metal tanpa menyentuh
implan. Irigasi dengan salin dingin untuk
mencegah dehidrasi tulang. Selanjutnya
dilakukan perawatan permukaan implan. Pertama
permukaan implan dekontaminasi dengan
aplikasi asam sitat, tetrasiklin, klorheksidin dan
saline fisiologis. Pada daerah implan yang
terekspos, dilakukan implantoplasti kemudian
permukaan dipoles yang akan memfasilitasi
pemeliharaan jaringan peri-implan yang sehat.
Akhirnya, daerah bedah diirigasi dengan
klorheksidin 0,12% dan salin fisiologis.28
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 59 – 65
63
Terapi Antibiotik pada penyakit peri-implan
Pertanyaan klasik dari banyak penulis
mempertanyakan apakah penggunaan antibiotik
diindikasikan untuk penyakit peri-implan.25
Bascones menyarankan penggunaan antibiotik
untuk penyakit periodontal mempunyai banyak
fungsi : mengurangi kebutuhan bedah,
meningkatkan klinin pasien, meningkatkan
kesuksesan graft. Study Gutierrez Perez dkk.
menyimpulkan bahwa strategi perawatan pada
penyakit periodontal dan peri-implan sebaiknya
fokus pada penggunaan rasional terapi
antimikrobial, dan menyatakan pentingnya
pemberian antibiotik sistemik pada poket peri-
implan lebih dari 5 mm, karena antiseptik lokal
tidak dapat mencapai dasar poket.28
Amoksisilin-asam clavulanic adalah
pilihan perawatan untuk penyakit peri-implan
karena sensitivitas bakteri dan mempunyai
resisten yang rendah . Clindamycin dan
metronidasol juga diindikasikan, tetapi
efektivitas lebih kecil melawan residual
streptococcus dan actinomyces.28
Terapi antibiotik sebagai profilaksis pada
pemasangan implant
Satu dari banyak kontroversi dalam
implantologi adalah penggunaan antibiotik
secara preventif ketika dilakukan prosedur
pemasangan implan. Profilaksis antibiotik
merupakan pemberian sebelum atau pada saat
bedah untuk mencegah komplikasi lokal atau
sistemik. Tujuan pemberian tersebut untuk
mencegah terjadi\inya infeksi pada luka bedah
dengan mencapai konsentrasi antibiotik dalam
darah yang akan mencegah proliferasi bakteria
dan disseminasi.29
Ada 2 faktor dasar pertimbangan
pemberian profilaksis dalam odonto-
stomatology dan bedah mulut : prosedur invasif
sebagai prosedur yang akan merusak membran
biologik yang akan meningkatkan diseminasi
bakteri pada tubuh. Perawatan invasif resiko
tinggi seperti : anestesi intraligamen, ekstraksi,
re-implan dental, biops, insisi drainase,
bonegraft, kuretase akar, bedah periodontal,
bedah penempatan implan, bedah mukogingiva,
bedah endodontik dan apikoektomi, prosedur
shaping tulang, bedah preprostetik, bedah
orthogranti, pengurangan fraktur maksila, bedah
kelenjar saliva, bedah onkologi maksilofasial.29
Faktor lain adalah profil risiko pasien yang
merupakan parameter ke-2 dimana pasien
diklasifikan dalam 3 group yaitu pasien sehat,
pasien dengan faktor resiko infeksi lokal atau
sistemik, dan pasien dengan faktor risiko infeksi
lokal diikuti bakteremia. Pada pasien group 1
tidak diperlukan catatan, akan tetapi mengikuti
tipe penyakit yang termasuk dalam profil resiko
seperti peradangan sendi : rheumatois arthritis,
systemic lupus erythematous, immunosupresion
terhadap penyakit, obat, transplantasi dan
radioterapi, Diabetes Mellitus tipe I, infeksi
endocarditis, malnutrisi.30
Profilaksis antibioik direkomendasikam
untuk pasien resiko yang akan dilakukan
prosedur invasif resiko tinggi. Penggunaan
profilaksis antibiotik tidak jelas pada
implantologi. Probabilitas infeksi di sekeliling
implant secara fundamental tergantung dari
bagaimana traumatik dan berapa lama
pembedahan. Diyakini bahwa kehilangan
implant awal disebabkan karena kontaminasi
selama pemasangan implant. Ada 2 situasi
penggunaan antibiotik sebagai profilaksis : 1.
ketika pasien dengan faktor resiko sistemik
mayor dan 2. Jika bedah diperkirakan lama
dan/atau traumatik30,31.
PEMBAHASAN
Menurut Mantena skala penilaian kualitas
implan terbagi dalam 4 kriteria yaitu: 1. Implan
sukses, 2. Satisfactory survival, 3. Compromised
survival dan 4. implan failure. Kriteria 1 implan
sukses ditandai dengan tidak ada rasa sakit, tidak
ada mobilitas, kedalaman poket 2 mm, sedikit
kehilangan tulang dan tidak ada riwayat eksudat.
Kriteria 2 satisfactory survival ditandai dengan
tidak ada rasa sakit saat berfungsi, tidak ada
mobilitas, kedalaman poket 2-4 mm, sedikit
kehilangan tulang, tidak ada riwayat eksudat.
Kriteria 3 compromised survival ditandai dengan
terasa sakit pada keadaan berfungsi, tidak ada
mobilitas, kehilangan tulang > 4 mm, kedalaman
poket > 7 mm, ada riwayat eksudat. Kriteria 4
implan failure ditandai sakit dalam keadaan
berfungsi, mobilitas, kehilangan tulang >1/2
panjang implant, eksudat tidak terkontrol, tidak
bertahan lama dalam mulut.1
Beban mekanikal yang besar pada implant
menyebabkan peningkatan resorpsi tulang.
Osteosit meningkatkan kolagenase 1 (produksi
MMP-1 di bawah tekanan mekanik, yang
menginisiasi resorpsi tulang . MMP-1
mendegradasi tulang tipe I dan III kolagen, yang
merupakan struktur utama kolagen tulang.
Tarytate-resistant acid phosphatase dan
cathepsin K meningkatkan osteoklas selama
mekanik yang menginduksi resorpsi tulang.32
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 59 – 65
64
Perawatan Peri-implantitis kelas 1 berupa
pengurangan kedalaman poket dengan bedah,
flap mukoperiosteal dan reposisi apical flap,
permukaan implan harus bersih dan
dekontaminasi. Perawatan Peri-implantitis kelas
2 sama dengan kelas 1, tapi reposisis lebih ke
apikal, meninggalkan lebih permukaan implant
terbuka, dan memerlukan implantoplasti. Jika
terjadi resorpsi vertikal lokal 3 dinding atau
lebih, defek tulang direstorasi dengan tehnik
GTR. Pada kasus defek dengan satu atau 2
dinding, diperlukan osteoplasty atau bone
leveling untuk reposisi jaringan lunak.27
Perawatan Peri-implantitis kelas 3 dan 4
terjadi defek vertikal diperlukan tehnik GTR.
Diperlukan perawatan kombinasi seperti :
Osteoplasty + implantoplasti + apikal reposisi
flap, Closed GTR + graft + reposisis koronal
flap, Semiopen atau ransgingival GTR +
implantoplasti + reposisi flap apikal.27
KESIMPULAN
Tingkat kesuksesan dan kestabilan dental
implan meskipun cukup tinggi, tetapi kegagalan
implan tetap terjadi. Faktor etiologi kegagalan
implan awal disebabkan oleh trauma bedah
disertai volume dan kualitas tulang yang tidak
baik, sedangkan etiologi kegagalan lanjut
disebabkan oleh trauma oklusal yang besar,
pembuatan restorasi yang tidak baik.
Perawatan kerusakan tulang awal di
sekeliling implan dapat dilakukan dengan
mekanik debridemen, terapi antimikroba, dan
terapi regenerasi yang merupakan kunci untuk
menyelamatkan kegagalan awal implan.
DAFTAR PUSTAKA
1. Mantena SR, Gotlumukkala SNVS, Sajjan S,
Rama Raju A, Rao B, Iyer M. Implant
Failures. Diagnosis and Management. Int J
Clin Implant Des 2015; 1(2): 51-59
2. El Askary AS, Meffert RM, Griffin T. Why
do dental implans fail? (part 1). Implant Dent
1999:8:265-77.
3. Esposito M, Hirsch JM, Lekholm U.
Thomsen P. Biological factors contributing of
osseointegrated oral implants (1) Success
Criteria and Epidemiology. Eur J Oral Sci
1998;106:527-51.
4. Alberktsson T, Zarb G, Worthington P,
Eriksson AR. The long-term efficacy of
currently used dental implants: a review and
proposed criteria of success. Int J oral
Maxillofac Implants 1986;1(1):11-25
5. Iacono VJ. Committee on research, science
and therapy, the American academy of
periodontology. Dental Implants in
periodontal therapy. J Periodontol
2000;71(12):1934-1942.
6. Ericsson I, Nilner K. Early functional loading
using Branemark dental implants. Int J
Periodontics Restorative Dent 2002;22(1):9-
19.
7. O’Mahony A, Bowles Q, Woolsey G,
Robinson SJ, Spencer P. stress distribution in
the single unit osseointegrated dental implant
finite element analysis of axial and off-axial
loading. Implant Dent 2009;9(3):207-218.
8. O’Sullivan D, Sennerby L, Meredith N.
Measurements comparing the initial stability
of five designs of dental implants: a human
cadaver study. Clin Implant Dent Relat Res
2002;2(2):85-92.
9. Lumbikaninda N, Sammons R. Bone cell
attachment to dental implant of different
surface characteristics. Int J Oral Maxillofac
Implants 2001;16(5):627-636.
10. Garber DA. The esthetic dental
implant:letting restoration be the guide. J Am
Dent Assoc 1996;22(1):45-50.
11. Jaffin RA, Berman CL. The excessive loss of
Branemark fixtures in type IV bone:a 5-year
analysis. J Periodontol 1991;62(1):2-4.
12. Jacobsson M, Tjellstrom A, Thom A, Klinge
B. sen P, Alberktsson T, Turesson I.
Integration of titanium implants in irradiated
bone. Histological and clinical study. Ann
Otol Rhinol Laryngol 1988;97:377-380.
13. Quirynen M, De Soete M, van Steenberg he
D. Infectious risk for oral implants : a review
of literature. Clin Oral Imp. Res 2002;13:1-19
14. Misch C. Dental Implant Prosthetics. 2nd ed.
St. Louis: Mosby. 2014. Page 8-28.
15. Kreisler M. Kohnen W, Marinello C, Schoof
J, Langnau E, Jansen B, d’Hoedt B.
Antimicrobial efficacy of semiconductor laser
irradiation on implant surfaces. Int J Oral
Maxillofac Implants 2003;18(5): 706-11.
16. Ellegard B, Baelum V, Karring T. Implant
Therapy in Periodontally compromised
patients. J Clin Oral Impl Res 1997:8:180-88.
17. Karoussis IK, Salvi GE, Heitz-Mayfield LJ,
Bragger U, Hammerle CH, Lang NP. Long-
term implant prognosis inpatients with and
without a history of chronic periodontitis: a
10-year prospective cohort study of the ITI
Dental Implant. Clin Oral Implants Res
2003;14(3):329-39.
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1, hal 59 – 65
65
18. Neukam FW, Flemmig TF. Local and
systemic conditions potentially compromising
osseointegration. Consesnsus report of
working group 3. Clin Oral Implants Res
2006;17 Suppl 2:160-2.
19. Hard CR, Grondahl K, Lekholm U,
wennstrom JL. Outcome of implant therapy in
relation to experience loss of periodontal bone
support: a retrospective 5-year study. Clin
Oral Implants Res 2002;13(5):488-94
20. Sheldon W, Harold FM, Shigeru O. Implant
Survival to 36 months as related to length and
diameter.Annals of Periodontology
2000;5:22-31.
21. Haanaes HR. Implants and infections with
special reference to oral bacteria. J od Clin
Periodontol 1990;17:516-24.
22. Gottlow J, Nyman S, Lindhe J, Karring R,
wennstrom J. New attachment formation in
the human periodontium by guided tissue
regeneration. J Clin Periodontol 1986;13:604-
16.
23. Mombelli A, Muhle T, Bragger U, Lang NP,
Burgin WP. Comparison of periodontal and
peri-implan probing by depth-force pattern
analysis. Clin Oral Implant Res 1997;
8(6):448-454.
24. Leonhardt A, Renvert S, Dahlen G. Microbial
findings at failing implants. Clin Oral Implant
Res 1999;10(5):339-45.
25. Bascones MA, Aquirre Urizar JM, Bermenjo
FA.Consensus statement on antimicrobial
treatment of odontogenic bacterial infections.
Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2004;9:363-
76.
26. Slot J, Bragd L, Wikstrom M, Dahlen GI.
The occurrence of Actinobacillus
actinomyceemcomitans, Bacteroides
gingivalis and Bacteroides intermedius in
destructive periodontal disease in adults. J
Clin Periodontol 1986;13(6):570-7.
27. Jovanovic SA. Diagnosis and treatment of
peri-implant disease. Curr Opin Periodontol
1994;2:194-204.
28. Guiterrez JL, Bagan JV, Bascones A, Liamas
R, Liena J, Morales A, Noguerol B, Planelis
P, Prieto J. Salmeron JL. Consensus
document on the use of antibiotic prophylaxis
in dental surgery and procedures. Med Oral
Patol Oral Cir Bucal 2006;11(2):188-205.
29. Van Oosterwyk H, Duyck J, Vander Sloten J,
van der Perre G, Naert I. Peri-implan bone
tissue strains in cases of dehiscence: a finite
element study. Clin Oral Implant Res
2002;13(3):327-33.
30. Esposito M, Coutlthard P, Oliver R, Thomas
P, Worthington HV. Antibiotics to prevent
complications following dental implant
treatment. Cochrane Database Sys Rev
2003;3:4152.
31. Espsito M, Hirsch JM, Lekholm U, Thomsen
P. Biological factors contributing to failure of
osseointegrated oral implants (1). Success
criteria and epidemiology. Eur J Oral Sci
1998;106:527-51.
32. Redlich M, Reichenberg E, Harari D, Zaks B,
Shoshan S, Palmon A. The effect of
mechanical force on mRNA levels of
collagenase, collagen type I, and tissue
inhibition of metalloproteinases in gingivae of
dogs. J dent Res 2001;80(12):2080-84.
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5 No.1, hal 66 – 73
66
Prevalensi Premature Loss Gigi Molar Kedua Sulung Dan Gambaran Maloklusi
Kajian pada Pasien ortodonti RSGM Universitas Trisakti tahun 2013– 2016
(Laporan Penelitian)
Yuniar Zen1, Krisnadya Dewa Yanti2
1Staf Pengajar Bagian Ortodonti FKG Usakti
2Mahasiswa Program Profesi Kedokteran Gigi Universitas Trisakti
ABSTRACT
Background: The premature loss of the primary second molar can cause first permanent molar mesial
drifting and result in loss of space for second premolar to erupt. Space loss can reduce arch length
required for succeeding tooth, tooth rotation, arch asymmetry and hence predisposes of malocclusion.
Objective: To provide the description of deciduous second molar premature loss in the classification
of Angle malocclusion. Method: Descriptive observational study using medical record and study
model on orthodontic patient at RSGM Trisakti University FKG year 2013 - 2016 with premature loss
of deciduous second molars as etiology. Result: Prevalence rates of premature loss of second
deciduous second molar in patients with age range between 7 - 10 years are 13% . The rates of
children age 7 years (16%), age 8 years (31%), age 9 years (32%), and age 10 years (21%). By
gender: female 56.5% and male 43.5%. Premature loss tooth 75 is 52%, 85 is 39%, 55 is 6% and 65 is
3%. The most common deciduous second molars premature loss is in the mandible (92%) then in both
(mandible and maxillary) (5%) and in the maxillary (3%). Premature loss of tooth 55 causes class I
malocclusions (75%) and class II malocclusions (25%). Premature loss of tooth 65 and 85 only causes
class I malocclusion and premature loss of 75 causes class I malocclusion (97%) and class III
malocclusions (3%).Conclusions: The prevalence of deciduous second molar premature loss is 13%,
and molar relationships most commonly found are class I.
Key Words: Premature loss, deciduous second molars, malocclusion
PENDAHULUAN
Maloklusi adalah suatu penyimpangan dari
oklusi ideal yang tidak dapat diterima secara
estetik ataupun fungsional.1 Maloklusi dapat
menyebabkan gangguan estetis wajah, gangguan
bicara, gangguan sendi temporomandibular,
terjadinya karies dan penyakit periodontal.2,3,
Prevalensi maloklusi di Indonesia masih sangat
tinggi, laporan hasil Riset Kesehatan Dasar
(Riskesdas) Nasional tahun 2013 menyatakan
bahwa prevalensi maloklusi di Indonesia sekitar
80% dari jumlah penduduk, dan merupakan salah
satu masalah kesehatan gigi dan mulut yang
cukup besar.4 Terjadinya maloklusi dapat
dipengaruhi oleh beberapa faktor etiologi, salah
satu satunya adalah premature loss.5
Premature loss merupakan keadaan gigi
sulung yang hilang atau tanggal sebelum gigi
penggantinya mendekati erupsi yang disebabkan
karena karies, trauma dan kondisi sistemik.6
Premature loss dapat menyebabkan maloklusi
tergantung pada jenis gigi yang hilang dan pada
usia berapa gigi tersebut hilang.7 Premature loss
gigi molar kedua sulung berkontribusi besar pada
perkembangan gigi berjejal di bagian posterior
lengkung dental.8 Premature loss gigi molar
kedua sulung menyebabkan gigi molar pertama
sulung bergeser ke arah mesial (mesial drifting),
hilangnya ruang untuk erupsi gigi premolar
kedua, pengurangan ruang Leeway, kontak
prematur dan gangguan oklusal, serta gigitan
silang posterior.9
Mesial drifting gigi molar permanen
pertama dapat menyebabkan maloklusi karena
pada klasifikasi maloklusi Angle hubungan
molar pertama merupakan kunci oklusi. Ada tiga
kelas dalam klasifikasi angle yaitu kelas I, II, dan
III. Dasar dari klasifikasi Angle adalah hubungan
molar pertama permanen, yaitu tonjol
mesiobukal (mesiobuccal cusp) gigi molar
pertama rahang atas berada pada bukal groove
gigi molar pertama rahang bawah.10
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5 No.1, hal 66 – 73
67
13%
87%
Premature lossgigi molar keduasulung
Bukan Prematureloss gigi molarkedua sulung
Penelitian yang dilakukan di Medan tahun
2015 menyatakan bahwa 32,5% pasien
mengalami premature loss molar sulung,11 selain
itu penelitian yang dilakukan oleh Hanindira
tahun 2016 di RSGM FKG Universitas Trisakti
menunjukan prevalensi premature loss sebesar
18,5% dengan presentase premature loss gigi
insisivus kedua sulung 30%, gigi insisivus
pertama sulung 21,25%, gigi molar kedua sulung
25%, gigi molar pertama sulung 12,50%, dan
gigi kaninus sulung 11,25%.12
Berdasarkan hasil penelitian tersebut di
atas, menunjukan bahwa prevalensi premature
loss gigi molar kedua sulung cukup tinggi. Gigi
molar kedua sulung sangat berpengaruh pada
perkembangan oklusi gigi karena hubungan
molar pertama permanen rahang atas dan rahang
bawah bergantung pada hubungan distal gigi
molar kedua sulung rahang atas dan rahang
bawah (flush terminal plane).10
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan
untuk mengetahui lebih jauh tentang prevalensi
premature loss molar kedua sulung dan
gambaran hubungan molar menurut klasifikasi
Angle sehingga bisa mendapatkan diagnosis dan
rencana perawatan yang tepat. Serta dapat
memberikan manfaat guna meningkatkan
pelayanan kesehatan gigi dan mulut serta
memberi informasi kepada dokter gigi dan
masyarakat agar dapat meningkatkan
pengetahuan serta perhatian orang tua terhadap
kesehatan gigi dan mulut terutama tentang
pencegahan terjadinya premature loss gigi molar
kedua sulung.
METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini merupakan penelitian
observasional deskriptif menggunakan
rancangan penelitian cross sectional. Penelitian
dilakukan di Bagian Ortodonti RSGM FKG
Universitas Trisakti pada bulan Oktober –
November 2017.
Sampel pada penelitian ini adalah rekam
medik dan model studi pasien ortodonti RSGM
FKG Universitas Trisakti periode tahun 2013 –
2016. Dengan perkiraan prevalensi premature
loss sebesar 18,5% dan presisi penelitian sebesar
10%, maka besar sampel yang dibutuhkan adalah
sebanyak 57.13
Kriteria inklusi adalah rekam medik dan
model studi pasien ortodonti RSGM FKG
Universitas Trisakti tahun 2013 –2016 dengan
etiologi premature loss gigi molar kedua sulung,
model studi lengkap rahang atas dan rahang
bawah, dan model studi pasien pada periode gigi
bercampur. Kriteria eksklusi adalah rekam medik
dengan data tidak lengkap dan model studi rusak
atau patah.
Definisi operasional variabel premature
loss adalah gigi molar kedua sulung yang hilang
lebih dari enam bulan sebelum waktu erupsi gigi
permanen penggantinya pada rahang atas atau
rahang bawah. Pemeriksaan dilakukan dengan
melihat rekam medik pasien kemudian
mencocokkan dengan melihat foto panoramik
dengan keadaan gigi molar kedua sulung hilang
dan benih gigi premolar kedua masih berada di
dalam tulang. Usia kronologis pasien yang
dijadikan sampel adalah usia erupsi gigi yang
dilihat berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun
kelahiran dimulai sejak awal kelahiran hingga
pasien berkunjung ke RSGM FKG Universitas
Trisakti untuk mendapatkan perawatan.
HASIL
Setelah dilakukan seleksi sesuai dengan
kriteria inklusi dan eksklusi terhadap 480 rekam
medik, didapatkan sebanyak 62 rekam medik
yang memiliki etiologi premature loss gigi molar
kedua sulung dan 418 rekam medik lainnya
memiliki etiologi selain premature loss gigi
molar kedua sulung, yaitu seperti presistensi gigi
sulung, kebiasaan buruk atau premature loss
dengan jenis gigi lain selain molar kedua sulung,
sehingga didapatkan prevalensi premature loss
gigi molar kedua sulung pada pasien ortodonti di
RSGM FKG Universitas Trisakti sebesar 13%
(Gambar 1).
Gambar 1. Presentase premature loss gigi molar
kedua sulung pada pasien ortodonti RSGM Trisakti
tahun 2013 - 2016
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
terdapat 62 pasien ortodonti di RSGM FKG
Universitas Trisakti pada tahun 2013 hingga
2016 yang memiliki etiologi premature loss gigi
molar kedua sulung. Pada tahun 2013 ada 11
pasien (2,29%), tahun 2014 ada 24 pasien
(5,09%), tahun 2015 22 pasien (4,58) dan pada
tahun 2016 5 pasien (1,04%) (tabel 1).
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5 No.1, hal 66 – 73
68
97%
1.5%1.5%
kelas I
Kelas II
kelas III
Tabel 1. Distribusi premature lossgigi molar kedua
sulung pasien ortodonti RSGM FKG Universitas
Trisakti berdasarkan tahun.
Tahun Frekuensi Presentase (%)
2013 11 2.29%
2014 24 5.09%
2015 22 4.58%
2016 5 1.04%
Total 62 13%
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pasien ortodonti di RSGM FKG Universitas
Trisakti pada tahun 2013 hingga 2016 yang
memiliki etiologi premature loss gigi molar
kedua sulung memiliki hubungan molar kelas I
sebesar 97%, hubungan molar kelas II sebesar
1,5% dan hubungan molar kelas III sebesar 1,5%
(Gambar 2).
Gambar 2. Distribusi hubungan molar menurut
klasifikasi Angle
Distribusi premature loss berdasarkan
jenis kelamin menunjukkan bahwa dari 62 rekam
medik yang didapat, pasien yang mengalami
premature loss gigi molar kedua sulung dengan
jenis kelamin laki – laki adalah sebanyak 27 anak
(43,5%) dan pasien yang mengalami premature
loss gigi molar kedua sulung dengan jenis
kelamin perempuan sebanyak 35 anak (56,5%)
(Tabel 2).
Tabel 2. Distribusi premature lossgigi molar kedua
sulung pasien ortodonti RSGM FKG Universitas
Trisakti berdasarkan jenis kelamin.
Jenis Kelamin Frekuensi Presentase (%)
Laki – laki 27 43,5%
Perempuan 35 56,5%
Total 62 100%
Berdasarkan jenis kehilangan gigi, dari 66
gigi molar kedua sulung yang mengalami
premature loss, kehilangan gigi terbanyak adalah
kehilangan gigi 75 yaitu sebanyak 34 gigi (52%),
kemudian gigi 85 sebanyak 26 gigi (39%), lalu
gigi 55 sebanyak 4 gigi (6%) dan yang paling
sedikit mengalami premature loss adalah gigi 65
yaitu sebanyak 2 gigi (3%) (Tabel 3).
Tabel 3. Distribusi frekuensi premature loss gigi
molar kedua sulung berdasarkan jenis gigi yang
hilang
Berdasarkan letak kehilangan gigi, dari 66
gigi molar kedua sulung yang mengalami
premature loss, kehilangan gigi terbanyak adalah
kehilangan gigi pada rahang bawah yaitu
sebanyak 92%, pada kedua sisi lengkung rahang
yaitu pada rahang atas dan rahang bawah sebesar
5% dan pada rahang atas sebanyak 3%. (Gambar
3)
Gambar 3. Presentase premature loss gigi molar
kedua sulung pasien ortodonti RSGM FKG
Universitas Trisakti berdasarkan letak gigi yang
hilang
Dilihat dari rentang usia antara usia 7 – 10
tahun pada pasien ortodonti di RSGM Fakultas
Kedokteran Gigi Universitas Trisakti yang
memiliki etiologi premature loss gigi molar
kedua sulung, didapatkan sebanyak 10 anak
(16%) mengalami premature loss gigi molar
kedua sulung di usia 7 tahun. Sebanyak 19 anak
(31%) mengalami premature loss gigi molar
kedua sulung pada usia 8 tahun, yang mengalami
premature loss gigi molar kedua sulung di usia 9
tahun sebanyak 20 anak (32%) dan yang
mengalami premature loss gigi molar kedua
3%
92%
5%
Premature
loss
Frekuensi
kehilangan gigi
Presentase
(%)
Gigi 55 4 6%
Gigi 65 2 3%
Gigi 75 34 52%
Gigi 85 26 39%
Total 66 100%
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5 No.1, hal 66 – 73
69
16%
31%32%
21%
0%
10%
20%
30%
40%
7 tahun 8 tahun 9 tahun 10 tahun
100%
0% 0%0%
50%
100%
150%
kelas I kelas II kelas III
97%
0% 3%
0%
50%
100%
150%
kelas I Kelas II Kelas III
sulung pada usia 10 tahun sebanyak 13 anak
(21%). Pada penelitian ini usia 9 tahun
merupakan usia paling banyak ditemukan
premature loss gigi molar kedua sulung, dan
usia 7 tahun merupakan usia paling sedikit yang
ditemukan premature loss gigi molar kedua
sulung (Gambar 4).
Gambar 4. Distribusi premature loss gigi molar kedua
sulung pasien ortodonti RSGM FKG Universitas
Trisakti berdasarkan rentang usia
Premature loss gigi molar kedua sulung
dapat menyebabkan maloklusi kelas I, maloklusi
kelas II maupun maloklusi kelas III. Premature
loss gigi 55 menyebabkan maloklusi kelas I dan
maloklusi kelas II dengan hubungan molar kelas
I sebesar 75% dan hubungan molar kelas II
sebesar 25%. Pada premature loss gigi 55 tidak
menyebabkan maloklusi kelas III (Gambar 5).
Gambar 5. Distribusi premature loss gigi 55
berdasarkan hubungan molar menurut klasifikasi
Angel
Premature loss gigi 65 hanya
menyebabkan maloklusi kelas I (100%) dan tidak
menyebabkan maloklusi kelas II maupun
maloklusi kelas III (Gambar 6).
Gambar 6. Distribusi premature loss gigi 65
berdasarkan hubungan molar menurut klasifikasi
Angel
Premature loss gigi 75 menyebabkan
maloklusi kelas I dan kelas III dengan hubungan
molar kelas I sebesar 97% dan hubungan molar
kelas III sebanyak 3%. Pada premature loss gigi
75 tidak menyebabkan maloklusi kelas II
(Gambar 7).
Gambar 7. Distribusi premature loss gigi 75
berdasarkan hubungan molar menurut klasifikasi
Angel.
Premature loss gigi 85 hanya
menyebabkan maloklusi kelas I (100%) tidak
menyebabkan maloklusi kelas II dan maloklusi
kelas III (Gambar 8).
Gambar 8. Distribusi premature loss gigi 75
berdasarkan hubungan molar menurut klasifikasi
Angel.
75%
25%
0%0%
20%
40%
60%
80%
kelas I kelas II kelas III
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5 No.1, hal 66 – 73
70
PEMBAHASAN
Premature loss gigi molar kedua sulung
dapat menyebabkan perubahan lengkung karena
terjadi pergerseran ke arah mesial (mesial
drifting) dari gigi molar permanen pertama
sehingga dapat menghambat erupsi dari premolar
kedua, yang berakibat impaksi atau
menghasilkan posisi gigi yang abnormal.15,16
Oleh karena itu premature loss molar kedua
sulung sebagai etiologi dari maloklusi ini penting
untuk diketahui guna penentuan rencana
perawatan ortodonti.17 Informasi dasar mengenai
prevalensi premature loss gigi sulung dibutuhkan
agar dapat mengurangi tingkat maloklusi dengan
perawatan gigi yang sistematis dan terorganisir.18
Penelitian mengenai premature loss sudah
banyak dilakukan di berbagai negara, dengan
hasil yang beragam.16,17 Berdasarkan hasil
penelitian yang telah dilakukan pada 62 rekam
medik di bagian ortodonti RSGM FKG
Universitas Trisakti, menunjukan bahwa
prevalensi premature loss gigi molar kedua
sulung pada pasien ortodonti sebesar 13%. Hasil
penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian
yang dilakukan di kota Medan menunjukkan
prevalensi premature loss gigi molar kedua
sulung lebih besar yaitu 32,5%,11 berbeda juga
dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh
Hanindira tahun 2016 di RSGM FKG
Universitas Trisakti yang menunjukan presentase
premature loss gigi molar kedua sulung sebesar
25%.12 Apabila dibandingkan dengan hasil
penelitian di Medan dan hasil penelitian
Hanindira, hasil penelitian saat ini lebih rendah,
hal ini bisa dikarenakan jumlah sampel yang
digunakan berbeda atau juga bisa disebabkan
karena tingkat kesadaran pasien dan orang tua
pasien tentang kebersihan gigi dan mulut serta
penyuluhan atau promosi preventif yang
dilakukan oleh RSGM FKG Universitas Trisakti
meningkat.
Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa terjadi
peningkatan pada pasien yang mengalami
premature loss gigi molar kedua sulung di
bagian ortodonti RSGM Universitas Trisakti dari
tahun 2013 ketahun 2014 sebesar 2,8% dari 11
pasien menjadi 24 pasien. Namun dari tahun
2014 ke tahun 2015 terjadi penurunan sebesar
0,51% dan penurunan semangkin meningkat dari
tahun 2015 ke tahun 2016 yaitu sebesar 3,54%.
Hal ini berarti setiap tahunnya dari tahun 2014
sampai tahun 2016 pasien yang mengalami
premature loss gigi molar kedua sulung semakin
berkurang. Hal ini bisa disebabkan karena dental
health education (DHE) atau promosi preventif
yang dilakukan oleh RSGM FKG Universitas
Trisakti cukup berhasil.
Pasien ortodonti di RSGM FKG
Universitas Trisakti pada tahun 2013 hingga
2016 yang memiliki etiologi premature loss gigi
molar kedua sulung dengan hubungan molar
kelas I Angle sebesar 97%, hubungan molar
kelas II Angle sebesar 1,5% dan hubungan molar
kelas III Angle sebesar 1,5%, hal ini sesuai
dengan hasil penelitian mengenai maloklusi dan
premature loss gigi sulung yang dilakukan oleh
Saloom di Baghdad yang menunjukkan bahwa
premature loss gigi molar pertama dan molar
kedua sulung dapat mengakibatkan maloklusi
Angle kelas I, kelas II dan kelas III.18 Hasil
penelitian ini juga sesuai dengan penelitian
Aslam dkk yang menyatakan bahwa maloklusi
Angle yang paling banyak adalah maloklusi
Angle kelas I.19
Berdasarkan jenis kelamin, distribusi
pasien ortodonti RSGM Fakultas Kedokteran
Gigi Universitas Trisakti yang mengalami
premature loss molar kedua sulung pada
penelitian ini lebih banyak dialami oleh pasien
perempuan yaitu sebanyak 35 anak (56,5%) dan
pasien yang mengalami premature loss gigi
molar kedua sulung dengan jenis kelamin laki –
laki sebanyak 27 anak (43,5%). Hal ini sesuai
dengan penelitian Hanindira yang menyatakan
bahwa pasien yang banyak berkunjung ke bagian
ortodonti di RSGM Fakultas Kedokteran Gigi
Universitas Trisakti adalah pasien perempuan12.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
berdasarkan letak kehilangan gigi, dari 66 gigi
molar kedua sulung yang mengalami premature
loss, kehilangan gigi terbanyak adalah
kehilangan gigi 75 yaitu sebanyak 34 gigi (52%),
kemudian gigi 85 sebanyak 26 gigi (39%), lalu
gigi 55 sebanyak 4 gigi (6%)dan yang paling
sedikit mengalami premature loss adalah gigi 65
yaitu sebanyak 2 gigi (3%). Hasil penelitian ini
sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan
oleh Cavalcanti dkk yang menyatakan bahwa
premature loss gigi molar kedua sulung paling
banyak adalah premature loss gigi 75.20
Premature loss gigi molar kedua sulung
berbahaya bagi pertumbuhan gigi permanen
karena gigi molar kedua sulung merupakan
panduan posisi gigi molar permanen pertama
yang menjadi kunci oklusi.10 Premature loss gigi
molar kedua sulung dapat disebabkan oleh
beberapa hal seperti karies atau ekstraksi gigi.
Premature loss gigi molar paling banyak
disebabkan oleh karies.6,21 Gigi yang rusak akibat
karies yang besar dan tidak dapat dilakukan
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5 No.1, hal 66 – 73
71
perawatan akan menjadi sumber infeksi jika
tidak dilakukan ekstraksi, hal ini juga merupakan
salah satu penyebab dari premature loss. Anak –
anak biasanya menyukai makanan yang manis,
tingginya kandungan gula dalam minuman dan
makanan yang manis dapat dikaitkan dengan
karies gigi. Oleh karena itu peran orang tua
sangat penting untuk menanamkan perilaku yang
sehat pada anak-anak mereka sejak usia dini.22
Berdasarkan letak gigi yang hilang,
premature loss terbanyak adalah premature loss
gigi molar kedua sulung pada rahang bawah
(92%) kemudian premature loss gigi molar
kedua sulung pada kedua lengkung rahang yaitu
rahang atas dan rahang bawah (5%) dan paling
sedikit terjadi pada rahang atas (3%). Hasil
penelitian ini sejalan dengan pernyataan pada
hasil penelitian Ahamed dkk., yang menyatakan
bahwa premature loss terbanyak dialami pada
rahang bawah,23 namun ada perbedaannya yaitu
setelah premature loss yang terbanyak pada
rahang bawah adalah pada rahang atas dan yang
paling sedikit adalah pada kedua lengkung
rahang yaitu rahang atas dan rahang bawah.23
Hasil penelitian ini ada perbedaan dengan hasil
penelitian Ahamed dkk kemungkinan
dikarenakan jumlah sampel yang digunakan
berbeda sehingga ada perbedaan pada jumlah
kehilangan gigi yang premature loss.
Prevalensi premature loss gigi molar
kedua sulung pada pasien ortodonti RSGM FKG
Universitas Trisakti dilihat berdasarkan rentang
usia adalah terbesar di usia 9 tahun yaitu
sebanyak 20 anak (32%), usia 8 tahun sebanyak
19 anak (31%), usia 10 tahun sebanyak 13 anak
(21%) dan usia 7 tahun merupakan usia paling
sedikit yang ditemukan premature lossgigi molar
kedua sulung yaitu sebanyak 10 anak (16%).
Hasil ini berbeda dengan penelitian penelitian
Hanindira yang menyatakan bahwa premature
loss paling sering terjadi pada usia 8 tahun,12
tetapi penelitian ini sejalan dengan penelitian
Cavalcanti dkk yang menyatakan bahwa
premature loss paling sering terjadi pada usia 9
tahun.20
Terdapat 23 gigi molar kedua sulung yang
mengalami premature loss dari total 20 anak usia
9 tahun pada pasien ortodonti di RSGM Fakultas
Kedokteran Gigi Universitas Trisakti.
Kehilangan gigi terbanyak adalah kehilangan
gigi 75 yaitu sebanyak 10 gigi (43,5%) kemudian
gigi 85 yaitu sebanyak 8 gigi (34,8%) lalu
kehilangan gigi 55 sebanyak 4 gigi (17,4%) dan
yang paling sedikit adalah kehilangan gigi 65
yaitu sebanyak 1 gigi (4,3%). Hasil ini
menunjukkan bahwa premature loss gigi molar
kedua sulung dapat terjadi pada rahang bawah,
rahang atas maupun pada kedua lengkung rahang
yaitu rahang atas dan rahang bawah.
Premature loss gigi molar kedua sulung
dapat menyebabkan maloklusi kelas I, kelas II
maupun kelas III, gambar 13 menunjukan bahwa
premature loss gigi 55 menyebabkan maloklusi
kelas I dan kelas II dengan hubungan molar kelas
I sebesar 75% dan kelas II sebesar 25%. Dari 66
sampel yang didapat, yang mengalami premature
loss gigi 55 adalah sebanyak 4 gigi. 3 gigi
diantaranya termasuk ke dalam klasifikasi kelas I
karena apabila dilihat dari model studi, terlihat
tonjol mesiobukal molar pertama rahang atas
berkontak dengan bukal groove molar pertama
rahang bawah dan 1 gigi lainnya termasuk
klasifikasi kelas II karena bila dilihat dari model
studi terlihat tonjol distobukal gigi molar
pertama rahang atas berkontak dengan bukal
groove molar pertama permanen rahang bawah.
Premature loss gigi 65 hanya
menyebabkan maloklusi kelas I. Hal ini
disebabkan karena dari 66 sampel yang didapat
hanya 2 gigi yang mengalami premature loss
gigi 65 dan bila dilihat dari model studi terlihat
tonjol mesiobukal molar pertama rahang atas
berkontak dengan bukal groove molar pertama
rahang bawah. Namun premature loss gigi 75
menyebabkan maloklusi kelas I dan kelas III
dengan hubungan molar kelas I sebesar 97% dan
hubungan molar kelas III sebanyak 3%. Dari 66
sampel pada penelitian ini, yang mengalami
premature loss gigi 75 adalah sebanyak 34 gigi.
Dari 34 gigi tersebut, 33 gigi termasuk dalam
klasifikasi kelas I karena dilihat dari model studi
terlihat tonjol mesiobukal molar pertama rahang
atas berkontak dengan bukal groove molar
pertama rahang bawah dan 1 gigi lainnya bila
dilihat dari model studi terlihat tonjol mesiobukal
molar pertama rahang atas berada lebih distal
dari bukal groove molar pertama rahang bawah.
Premature loss gigi 85 hanya
menyebabkan maloklusi kelas I. Hal ini
disebabkan karena dari 66 sampel yang didapat,
gigi yang mengalami premature loss gigi 85
sebanyak 26 gigi dan bila dilihat dari model studi
gigi tonjol mesiobukal molar pertama rahang atas
berkontak dengan bukal groove molar pertama
rahang bawah.
KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah
dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan
yaitu: prevalensi premature loss gigi molar
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5 No.1, hal 66 – 73
72
kedua sulung pada pasien ortodonti di RSGM
Universitas Trisakti sebesar 13%. Premature loss
gigi molar kedua sulung paling banyak dialami
oleh pasien berjenis kelamin perempuan. Usia 9
tahun merupakan usia paling banyak
ditemukannya premature loss gigi molar kedua
sulung yaitu sebesar 32%. Kehilangan gigi
terbanyak yaitu kehilangan gigi 75 sebesar 52%,
dan hubungan molar yang paling sering
ditemukan adalah hubungan molar kelas I
sebesar 97%.
DAFTAR PUSTAKA
1. Millet, Declan dan Richard W. Orthodontics
and Paediatric Dentistry. Sydney: Chruchill
Livingstone; 2000: 5.
2. Rakosi T, Jonas I, dan Graber TM.
Orthodontic Diagnotstic Color Atlas of
Dental Medicine. Ratheitschak HK. Wolf HF.
Editor. Thieme Medical Publisher Inc. 1993;
35 – 87.
3. Profit WR, Fields HW dan Sarver DM.
Contemporary Orthodontics. 5th Edition.
Canada. Elsevier. 2013; 3.
4. Samad R. dan Gazali S., Hubungan
Kebiasaan Mendorong Lidah, Menghisap Ibu
Jari dan Premature loss Terhadap Jenis
Maloklusi Murid SD di Kota Makassar.
Available from:
http://repository.unhas.ac.id/handle/12345678
9/20202. 2016.
5. Graber TM, Vanarsdall RL dan Vig KWL.
Orthodontics Current Principle and
Teqniques. 5th Edition. USA: Elsevier. 2012;
15
6. McDonald RE,Avery DR, Dean JA. Dentisry
for the child and adolescent.9th ed. St Louis :
Mosby: 2011. 150-3,220,518,559-63
7. Alexander SA, Askari M, Lewis P. The
premature loss of primary first molars: Space
loss to molar occlusal relationships and facial
patterns. Angle Orthod. 2015;85(2):218–223.
8. Al-Shahrani N, Al-Amri A, Hegazi F, Al-
Rowis K, Al-Madani A, Hassan KS. The
prevalence of premature loss of primary teeth
and its impact on malocclusion in the Eastern
Province of Saudi Arabia. Acta Odontol
Scand. 2015;73(7):544–549.
9. Pokorná H, Marek I, Kucera J, Hanzelka T.
Space Reduction After Premature loss of A
Deciduous Second Molar – Retrospective
Study. IOSR Journal of Dental and Medical
Sciences (IOSR-JDMS). November 2016.
15(11); 1 – 8.
10. Kusnoto J, Fajar HN, dan Haryanto AG.
Buku Ajar Orthodonti jilid 1. Jakarta: EGC.
2016; 92 – 212.
11. Harahap S. Prevalensi Premature loss Gigi
Molar Desidui pada Pasien Ortodonsia di
RSGMP FKG USU Tahun 2010-2014.
Available from:
http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/
55974. 2015
12. Hanindira M. Prevalensi Maloklusi Dengan
Etiologi Premature loss Gigi Sulung Pada
Pasien Ortodonti Di Rsgm Fkg Universitas
Trisakti ( Periode Tahun 2013 – 2015 ). 2017;
23 - 26.
13. Dahlan MS. Evidence Based Medicine Seri 3:
Langkah – Langkah Membuat Proposal
Penelitian Bidang Kedokteran dan Kesehatan.
Edisi II. Jakarta: CV Sagung Seto; 2016; 80.
14. Bhalajhi SI. Orthodontics The Art and
Science. 3rd edition. New Delhi: Arya (Medi)
Publishing House. Oktober 2003; 91 – 95.
15. Song K, Nam O, Kim M, Lee H, Choi S.
Management of Premature loss of Primary
Molars with Flexible Denture. J Korean Acad
Pediatr Dent. 2016. 43(2); 187 – 191.
16. Herawati H, Novita S, dan Rainisa DU.
Hubungan Premature loss Gigi Sulung
Dengan Kejadian Maloklusi Di Sekolah
Dasar Negeri Kota Cimahi. Journal of
Medicine and Health. Augustus 2015. 1(2):
156 – 169.
17. Murshid SA, Al-Labani MA,Aldhorae
KA,Rodis OM. Prevalence of prematurely
lost primary teeth in 5-10 year-old children in
Thamar City, Yemen : A cross-sectional
study. J Int Soc Preven Communit Dent 2016
; 6, Suppl S2: 126-30
18. Saloom HF. Early Loss of Deciduous Teeth
and Occlusion. Iraqi Orthod J. 2005;1(2):36–
39.
19. Aslam K, Nadim R, Rizwan S. Prevalence of
angles malocclusion according to age groups
and gender. Pakistan Oral Dent J.
2014;34(2):362-365.
20. Cavalcanti, A.L., Alencar, C.R.B.D., Bezerra,
P. and Granville-Garcia AF. Pediatric
dentistry prevalence of early loss of primary
molars in school children in Campina Grande,
Brazil. Pakistan Oral Dent J. 2008;28(1):113.
21. Law CS. Management Of Premature Primary
Tooth Loss in the Child Patient. CDA J.
2013;41(8):612–618.
22. López-Gómez SA, Villalobos-Rodelo JJ,
Ávila-Burgos L. Relationship between
premature loss of primary teeth with oral
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5 No.1, hal 66 – 73
73
hygiene, consumption of soft drinks, dental
care, and previous caries experience. Sci Rep.
2016
23. Ahamed SS, Krishnakumar R, Sugumaran D,
Reddy V, Mohan M, Rao A. Prevalence of
early loss of primary teeth in 5-10-year-old
school children in Chidambaram town.
Contemp Clin Dent. 2012;3(1):27-30.
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1
Tata Cara Penulisan
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu
Aturan umum:
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu hanya
menerima naskah asli yang belum pernah dipub-
likasikan di dalam maupun di luar negeri.
Naskah dapat di tulis dalam bahasa Indonesia atau
bahasa Inggris dengan gaya bahasa efektif dan
akademis.
Sistematika penulisan artikel:
Judul,
Hendaknya menggambarkan isi pokok tulisan
secara ringkas dan jelas, ditulis dalam bahasa
Indonesia dan bahasa Inggris. Judul terdiri dari
maksimal 15 kata. Nama Penulis, ditulis nama
penulis tanpa gelar, disertai instansi tempat penu-
lis bekerja.
Abstract
Ditulis dalam bahasa Inggris, tidak lebih dari
250 kata, font Times New Roman dengan ukuran
font 12 dan spasi 1, merupakan intisari seluruh
tulisan dan ditulis terstruktur sebagai berikut:
Laporan Penelitian: Pendahuluan, tujuan,
metode, hasil dan kesimpulan
Laporan Kasus: Pendahuluan, tujuan, kasus dan
penatalaksanaan kasus, dan kesimpulan
Tinjauan Pustaka: Pendahuluan, tujuan, tinjauan
pustaka, dan kesimpulan
Keywords, diletakkan di bawah abstrak 3-5 kata
kunci. Correspondence, Alamat korespondensi
yang berisi nama lengkap contact person, afili-
asi/nama institusi, alamat pos lengkap dengan
kode pos, dan alamat email.
Petunjuk penulisan LAPORAN PENELITIAN
Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah,
rumusan masalah serta tujuan penelitian dan
manfaat untuk waktu yang akan datang. Bahan
dan Metode, berisi penjelasan tentang ba-
han-bahan dan alat-alat yang digunakan, waktu,
tempat, teknik, dan rancangan percobaan. Metode
harus dijelaskan selengkap mungkin agar peneliti
lain dapat melakukan uji coba ulang. Acuan (ref-
erensi) diberikan pada metode yang kurang
dikenal. Hasil, dikemukakan dengan jelas bila
perlu dengan tabel, ilustrasi (gambar, grafik, dia-
gram) atau foto. Hasil yang telah dijelaskan
dengan tabel atau ilustrasi tidak perlu diuraikan
panjang-lebar dalam teks. Garis-garis vertikal
dibuat seminimal mungkin, agar memudahkan
penglihatan. Perhatikan:
1. Persamaan Matematis dikemukakan dengan
jelas. Jika simbol matematis tidak ada pada
word proccesor dapat ditulis menggunakan
pensil/pena dengan hati-hati. Kalau perlu beri
keterangan simbol dengan tulisan tangan (pen-
sil tipis).
2. Angka desimal ditandai dengan koma untuk
bahasa Indonesia dan titik untuk bahasa
Inggris.
3. Tabel, ilustrasi atau foto diberi nomor dan di-
acu berurutan dengan teks, judul ditulis dengan
singkat dan jelas. Keterangan diletakkan pada
catatan kaki, tidak boleh pada judul. Semua
singkatan atau kependekan harap dijelaskan
pada catatan kaki.
Pembahasan, menerangkan hasil penelitian,
bagaimana hasil penelitian yang dilaporkan dapat
memecahkan masalah, perbedaan dan persamaan
dengan penelitian terdahulu serta kemungkinan
pengembangannya. Kesimpulan dan saran dile-
takkan pada bagian akhir pembahasan yang
merupakan paragraf penutup.
Ucapan terima kasih, dapat ditujukan pada semua
pihak yang membantu bila memang ada dan harus
diterangkan sejelas mungkin. Diletakkan pada
akhir naskah, sebelum daftar pustaka.
Daftar Pustaka, disusun menurut sistem Vancou-
ver. Setiap nama pengarang diberi nomor urut
sesuai dengan urutan pemunculannya dalam
naskah, dan mencantumkan (a) untuk buku: na-
ma-nama penulis, editor (bila ada), judul lengkap
buku, kota penerbit, tahun penerbitan, volume,
edisi dan nomor halaman. (b) untuk terbitan
berkala: nama-nama penulis, judul tulisan, judul
terbitan (disingkat sesuai dengan Index Medicus),
tahun penerbitan, volume dan nomor halaman. (c)
acuan dari internet harus ditulis nama penyusun,
nama website/ blog, alamat website dan tanggal
akses internet. Pustaka yang diacu diusahakan
merupakan terbitan/produksi 10 (sepuluh) tahun
terakhir, kecuali memang merupakan hal yang
langka.
Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi Terpadu 2019, Vol.5, No.1
Petunjuk penulisan LAPORAN KASUS
Pendahuluan, meliputi latar belakang kasus,
permasalahan, kekhususan atau kelangkaan kasus,
tujuan laporan kasus dan manfaat untuk waktu
yang akan datang. Kasus, identifikasi pasien, an-
amnesa, keluhan utama, pemeriksaan ekstra oral,
intra oral, hasil pemeriksaan penunjang seperti
foto profil wajah, hasil rontgen foto dental atau
panoramik, hasil laboratorium dan diagnosa..
Tatalaksana Kasus, rencana terapi, penatalaksa-
naan kasus disertai foto, monitoring, evaluasi
klinis dan atau laboratoris, dan hasil perawatan
berikut penjelasannya. Pembahasan, men-
erangkan telaah teori dari hasil perawatan kasus
yang dilaporkan, bagaimana hasil perawatan kasus
tersebut dapat memecahkan masalah, perbedaan
dan persamaan dengan kasus-kasus terdahulu ser-
ta kemungkinan aplikasinya. Kesimpulan dan sa-
ran diletakkan pada bagian akhir pembahasan
yang merupakan paragraf penutup. Daftar
pustaka. Sama dengan di atas.
Petunjuk penulisan TINJAUAN PUSTAKA
Pendahuluan, meliputi latar belakang topik, per-
masalahan, kekhususan topik, tujuan tinjauan
pustaka dan manfaat untuk waktu yang akan da-
tang. Tinjauan pustaka, telaah teori dari berbagai
sumber acuan mutakhir. Pembahasan. men-
erangkan pemikiran penulis dari hasil telaah
pustaka, bagaimana hasil tsb dapat memecahkan
masalah, perkembangan dan aplikasinya. Sim-
pulan dan saran diletakkan pada bagian akhir
pembahasan yang merupakan paragraf penutup.
Daftar pustaka. Acuan yang digunakan untuk
artikel tinjauan pustaka usahakan minimal 25
(tiga puluh lima) buah, yang disusun menurut sis-
tem Vancouver. Tata cara sama dengan di atas.
Informasi penting lain Naskah yang dikirim diketik dalam CD dengan
program MS Word, disertai cetakan pada kertas
HVS ukuran A4 (210 x 297 mm) maksimal 12
halaman. Ukuran font 12 dengan jenis Times New
Roman, dengan spasi 1,5. Print out naskah dis-erahkan rangkap 2 (Dua).
Alamat pengiriman naskah:
Drg. Enrita Dian R SpKGA
FKG USAKTI Bagian IKGA Lt. 5
Jl. Kyai Tapa Grogol Kampus B FKG USAKTI Email: [email protected]
Perhatian:
Naskah yang telah diterima beserta semua ilustrasi
yang menyertainya menjadi milik sah penerbit,
serta tidak dibenarkan untuk diterbitkan dimana-
pun, baik secara keseluruhan atau sebagian, dalam
bentuk cetakan maupun elektronika tanpa ijin ter-
tulis dari penerbit. Semua data, pendapat, atau
pernyataan yang terdapat pada naskah adalah
merupakan tanggung jawab penulis. Penerbit dan
dewan redaksi tidak bertanggung jawab atau tidak
bersedia menerima kesulitan maupun masalah
apapun sehubungan dengan konsekuensi dari
ketidak akuratan, kesalahan data, pendapat, mau-pun, pernyataan tersebut.