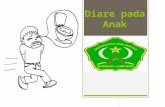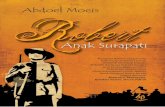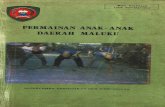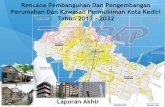KEBIJAKAN KOTA SURAKARTA MENUJU KOTA LAYAK ANAK DALAM PEMENUHAN KEADILAN RESTORATIF BAGI ANAK YANG...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of KEBIJAKAN KOTA SURAKARTA MENUJU KOTA LAYAK ANAK DALAM PEMENUHAN KEADILAN RESTORATIF BAGI ANAK YANG...
A. JUDUL
KEBIJAKAN KOTA SURAKARTA MENUJU KOTA LAYAK ANAK
DALAM PEMENUHAN KEADILAN RESTORATIF BAGI ANAK YANG
BERHADAPAN HUKUM (ABH).
B. ABSTRAK
Kota Layak Anak (KLA) merupakan tujuan pembangunan Pemerintah KotaSurakarta yang berpihak pada pemenuhan dan perlindungan hak anak. Digagas sejaktahun 2008 dengan lahirnya berbagai produk aturan hukum dan kelembagaan.Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS) dan Pusat PelayananTerpadu (PPT) di 51 kelurahan sebagai wadah layanan anak yang berhadapan hukum(ABH), salah satunya. Penanganan ABH yang berkeadilan restoratif, sesuai Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA),diperlukan untuk mengindarkan dampak negative dari proses peradilan formal.Efektifitas kinerja PTPAS dan PPT Kelurahan diupayakan melalui peningkatankapasitas personel dan sistem layanan yang saling integratif. ABH tidak hanyaterselesaikan masalah hukumnya, namun juga akar masalah yang mendorongnyamenjadi delinquency.
Kata kunci: anak berhadapan hukum, kota layak anak, keadilan restoratif,kebijakan.
C. PENDAHULUAN
Ratifikasi Konvensi Hak Anak tahun 1989 telah dilakukan oleh Pemerintah
Indonesia melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Tujuh tahun kemudian hadir
Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Pengkhususan
pengaturan bagi anak yang berhadapan dengan hukum telah menjadi kebutuhan.
Setiap tahun jumlah anak yang melakukan pelanggaran hukum meningkat. Data dari
Kementrian Hukum dan HAM RI tahun 2013, terdapat 123 anak Negara, 6 anak sipil,
dan 3.305 anak pidana. Tahun 2012 terdapat 248 anak negara, 21 anak sipil, dan
3.388 anak pidana1. Setiap tahunnya terdapat kurang lebih 3.500 anak yang
dihadapakan pada proses peradilan pidana di Indonesia.
Kasus yang banyak dilakukan anak adalah penganiayaan, pencurian, dan
kekerasaan seksual. Hukuman pidana penjara masih banyak menghiasi vonis hakim
bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Anak kemudian ditempatkan di rumah
penahanan atau lembaga pemasyarakatan sesuai wilayah hukum perkara. Dari 33
1 http://smslap.ditjenpas.go.id/public/arl/current/monthly/year/2012/month/12 . Diakses tanggal 26 Juni2014.
Kantor Wilayah Hukum dan HAM terdapat 415 rutan atau lapas. Propinsi Jawa
Tengah terbanyak jumlah rutan dan lapasnya, yakni 43.
Pasal 17 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak menyebutkan setiap anak yang dirampaas kebebasaanya berhak
untuk :
a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari
orang dewasa.
b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efekti dalam setiap
tahapan upaya hukum yang berlaku, misalnya bimbingan social dari pekerja
social, konsultasi dari psikiater atau psikolog, atau abntuan dari ahli bahasa.
c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang
obyektif dan tidak memihak dalam siding yang tertutup untuk umum.
Semangat isi pasal di atas sangat ideal, namun faktanya masih banyak anak
pidana yang ditempatkan bersama dengan orang dewasa. Di Indonesia hanya terdapat
18 lapas khusus anak, dimana penghuni seluruhnya adalah anak. Jumlah lapas anak
yang minim mengakibatkan banyak anak pidana ditempatkan di rutan atau lapas
umum. Berinteraksi dengan orang dewasa setiap harinya memberi peluang besar bagi
anak untuk menduplikasi perilaku negatif orang dewasa. Pasca menjalani vonis, anak
pidana mengalami tantangan besar dari masyarakat, yakni stigma. Pelabelan sebagai
anak nakal, mantan napi memberikan tekanan tersendiri bagi mereka. Fasilitas yang
mendukung tumbuh kembang anak masih terbatas seperti perpustakaan, tidak ada
pendidikan formal, tidak ada fasilitas rekreatif, sanitasi minim, hukuman tidak
mendidik bagi pelanggaran2.
Karakteristik anak yang melakukan pelanggaran pidana adalah laki-laki
daripada perempuan. Status ekonomi keluarga mereka minim. Pendapatan orang tua
tidak menentu. Buruh bangunan, sopir, pekerja rumah tangga, buruh pabrik adalah
gambaran pekerjaan orang tua mereka. Pendidikan anak pun banyak yang putus di
tengah jalan. Kondisi inilah yang jamak ditemui pada anak yang berkonflik dengan
hukum. Perilaku negative mereka tidak datang dengan tiba-tiba. Anak sebagai pribadi
yang masih labil, sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan dan orang dewasa yang
ada disekitarnya.
2 Sasmini, Diana Tantri Cahyaningsih, dan Erna Diah Kusumawati. 2013. Perlindungan danPemenuhan Hak-hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang Dititipkan di Rumah TahananNegada dan Lembaga Pemasyarakatan. Belum terpublikasi. Hal: 5.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
(UU SPPA) disahkan dan mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2014. Norma hukum ini
memberikan warna lain bagi proses peradilan anak yan berkonflik dengan hukum.
Ada kenaikan batasan umur anak yang dapat bertanggungjawab secara pidana
menjadi 12 tahun. Pada undang-undang sebelumnya, batasan umur anak yang dapat
bertanggungjawab pidana adalah 8 tahun. UU Nomor 11 Tahun 2012, anak dapat
dilakukan penahanan jika telah berumur 14 tahun. Angka 14 tahun pada anak berarti
telah remaja dan dianggap lebih matang berpikir.
Ruang lingkup pengaturan UU SPPA mencakup penyelesaian perkara anak
yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyidikan hingga pembimbingan
setelah menjalani hukuman pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari
anak yang berkonflik dengan hukum (AKH) atau pelaku, anak sebagai korban, dan
saksi. Pergeseran paradigma pemidanaan hadir dalam UU SPPA ini. Keadilan
retributive menekankan keadilan adalah pembalasaan. Anak hanya sebagai obyek.
Sedangkan keadilan restitutif bertumpu pada penggantian kerugian. Keadilan
restorative menjadi pilihan terbaik yang diadopsi dalam UU SPPA karena berfokus
pada pemulihan. Kepentingan korban diperhatian serta AKH dan masyarakat turut
terlibat dalam proses.
Pasal 1 Ayat (6) UU SPPA menyebutkan keadilan restorative adalah
penyelesaian perkara tindak pidana pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak
lain yang terlait untuk terlibat bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan
menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasaan. Anak
sebagai pelaku diberikan kesempatan untuk partisipasi dalam pemulihan kerugian
korban. Masyarakat juga turut berperan aktif mendukung upaya pemulihan ini.
Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
sejak tahun 2006 mendorong Kota Surakarta sebagai uji coba model Kota Layak
Anak (KLA). Program KLA ini merupakan turunan dari misi Indonesia Layak Anak
(IDOLA) dimana semua kabupaten dan kota harus melakukan perlindungan dan
pemenuhan hak anak sebagai wujud tanggungjwab negara terhadap generasi penerus
bangsa. Permeneg PPPA Nomor 12 Tahun 2011 terdapat 31 indikator sebuah kota
menjadi layak anak sesuai dengan isi Konvensi Hak Anak. Salah satu kluster dalam
indikator tersebut adalah perlindungan khusus yang mencakup situasi anak
mebutuhkan perlindungan khusus (AMPK), perkara anak berhadapan dengan hukum
yang diselesaikan dengan restorative justice, anak dalam situasi bencana, dan
pekerjaan terburuk anak.
Tahun 2010 terdapat 17 anak dan 2011 terdapat 19 anak dari Kota Surakarta
yang mendekam di Rutan Surakarta. Data tersebut berasal dari Pelayanan Terpadu
Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS) yang merupakan konsorsium terdiri dari
pemerintah dan organisasi penyedia layanan bagi perempuan dan anak. PTPAS
membelikan layanan holistic bagi anak yang berhadapan dengan hukum berupa
pendampingan hukum, rehabilitasi fisik dan mental anak. Bapermas PPPA KB Kota
Surakarta sebagai koordinator pelaksana PTPAS sejak tahun 2012 telah membentuk
Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) sebagai tangan panjang PTPAS di 51 kelurahan.
Harapannya PPT dapat berpartisipasi memberikan perlindungan bagi anak yang
berhadapan dengan hukum berbasis masyarakat di Kota Surakarta. Keanggotaan PPT
terdiri dari tokoh masyarakat dan perwakilan kelembagaan di masyarakat.
Harapannya PPT dapat menjadi gerbang pertama dalam merespon permasalahan anak
yang ada di lingkungan.
Hadirnya UU SPPA menjadi tantangan tersendiri bagi Kota Surakarta yang
pada tahun 2015 akan menjadi Kota Layak Anak. Penghargaan nindya dalam tahapan
KLA memberi kesempatan Pemkot Surakarta untuk meningkatkan kualitas
layanannya kepada anak yang berkonflik denngan hukum agar mendapatkan keadilan
restorative. Kepentingan terbaik bagi anak dan prinsip pemulihan menjadi pegangan
dalam penyusunan kebijakan yang responsive hak anak.
D. RUMUSAN MASALAH
Gambaran di atas mewakili situasi yang ada di masyarakat. Berdasar uraian
tersebut, penulis hendak menjawab permasalahan sebagai berikut:
Bagaimana kebijakan pemenuhan keadilan restoratif bagi anak yang
berhadapan hukum (ABH) oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam upaya menuju Kota
Layak Anak (KLA)?
E. LANDASAN TEORI
1. Tinjauan Hukum sebagai Sarana Rekayasa Sosial
Hukum mengabdi pada tujuan negara yang dalam pokoknya mendatangkan
kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya3. Pernyataan tersebut disampaikan oleh
Prof. Subekti dalam bukunya C.S.T. Kansil merupakan pemikiran hubungan
hukum dalam sebuah negara. Teori fungsi hukum dalam masyarakat dapat dilihat
dari dua sisi yakni kemajuan masyarakat dalam berbagai bidang memnutuhkan
aturan. Sisi kedua, hukum yang baik dapat mengembangkan masyarakat atau
mengarahkan perkembangan masyarakat4.
Lawrence W. Friedman menyatakan bahwa perubahan hukum yang kemudian
dapat mengubah suatu pandangan atau sikap dan kehidupan suatu masyarakat
berasal dari berbagai stimulus sebagai berikut5:
a) Berbagai perubahan secara evolutif terhadap norma-norma dalam masyarakat.
b) Kebutuhan dadakan dari masyarakat karena adanya keadaan khusus atau
keadaan darurat dalam ubungan dengan distribusi sumber daya atau hubungan
dengan standar baru tentang keadilan.
c) Atas inspirasi keompok kecil masyarakat yang dapat melihat jauh ke depan,
kemudian sedikit demi sedikit mempengaruhi pandangan dan cara hidup
masyarakat.
d) Ada ketidakadilan secara tehnikal hukum yang meminta diubahnya hukum
yang bersangkutan.
e) Ada ketidakkonsistenan dalam tubuh hukum yang juga meminta perubahan
terhadap hukum tersebut.
f) Ada perkembangan pengetahuan dan teknologi yang memunculkan bentukan
baru terhadap bidang hukum tertentu.
Fungsi hukum sebagai rekayasa sosial pertama kali dicetuskan oleh Roscoe
Pound yang menyatakan law is a tool pf social engineering. Teori ini teramsuk
dalam teori sosiologi jurisprudence yang mempelajari tentang pengaruh hukum
terhadap masyarakat6. Berdasarkan teori tersebut, pemahaman hukum terhadap
masyarakat ataupun masyarakat terhadap hukum dapat dilihat jelas posisinya.
Roscoe Pound menyatakan lebih lanjut bahwa sociological jurisprudence ditujukan
untuk memberi kemampuan bagi institusi hukum mempertimbangkan secara
3 C.S.T. Kansil. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.Hlm.414 H. Munir Fuady. 2003. Teori-teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum. Jakarta: Kencana. Hlm.2455 Ibid, hlm.2896 H. Abdul Manan. 2009. Aspek-aspe Perubahan Hukum. Jakarta: Kencana. Hal.19
menyeluruh juga cerdas mengenai fakta sosial yang disana hukum tersebut
berproses dan diaplikasikan7.
Teori sociological jurisprudence dapat dijadikan dasar menilai berlakunya
hukum di tengah masyarakat. Sisi efektivitasnya kekuatan berlakunya hukum
mengarah pada kepatuhan hukum dan daya penagruh hukum dalam persepsi
masyarakat adalah dua hal yang dilihat dalam hukum seabagai rekayasa sosial.
Tujuan social engineering adalah membangun suatu struktur masyarakat
sedemikian rupa sehingga secara maksimum dapat dicapai kepuasan akan kbutuhan
dan seminimum mungkin terjadi benturan8.
Roscoe Pound sendiri mengembangkan daftar kepentingan yang wajib
dilindungi oleh pranata hukum, yakni sebagai berikut9:
a) Kepentingan umum, yang teramsuk di dalamnya adalah kepentingan terhadapa
negara sebagai suatu badan yuridis dan kepentingan negara sebagai penjaga
kepentingan sosial.
b) Kepentingan perorangan terdiri darikepentingan pribadi baik fisik, kebebasan,
kemauan, kehormatan, kepercayaan, dan pendapat; hubungan domestic (orang
tua, anak, suami atau istri); kepentingan substansi berupa hak milik, kontrak,
pekerjaan, dan atau hubungan dengan orang lain.
c) Kepentingan sosial meliputi keamanan umum, keamanaan dari isntitusi sosial,
moral umum, pengamanan sumber daya sosial, kemajuan sosial, dan
kehidupan individual.
Tahapan yang diambil dalam social engineering bersifat sistematis dan
dimulai dari identifikasi masalah samapai dengan mencari jalan pemecahannya.
Perubahan hukum itu sendiri harus direncanakan dan merupakan sebuah kehendak
bersama sehingga dapat berjalan sesuai harapan. Rincian tahapannya terurai
demikian10:
a) Mengenal problem yang dihadapi seabaik-baiknya. Termasuk di dalamnya
mengenali masyarakat yang hendak menajdi sasaran pengggarapan dengan
seksama.
7 Philipe Nonet dan Philip Selznick. 2013. Hukum Responsif. Bandung: Nusa Media. Hal.838 Satjipto Raharjo. 2010. Sosiologi Hukum. Yogyakarta/: Genta Publishing. Hal. 3049 Ibid, hal.30510 Satjipto Raharjo, op.cit. hal.8
b) Memahami nilai-nilai yang ada di masyarakat. Sesi ini harus menentukan
sector mana yang akan dipilih karena masyarakat memiliki berbagai sector
yang majemuk.
c) Membuat hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk dilaksanakan.
d) Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur dampak-dampaknya
yang muncul.
2. Tinjauan Implementasi Kebijakan
Implementasi kebijakan merupakan sebuah upaya untuk mencapai tujuan
tertentu melalui sarana-sarana dalam urutan waktu tertentu11. Sebuah kebijakan
tidak hanya dirumuskan kemudian diwujudkan dalam peraturan positif yang tidak
dilaksanakan. Namun kebijakan memiliki keharusan untuk dilaksanakan agar
memiliki dampak atau terwujud tujuan yang diharapakan sejak awal.
Proses implementasi kebijakan baru dapat dimulai jika tujuan awal
kebijakan telah ditentukan. Program kerja yang akan dilaksanakan juga telah
disusun dengan mata. Anggaran untuk implementai juga telah dialokasikan.
Pengertian implementasi kebijakan dapat dipahami secara luas sebagai alat
administrasi hukum dimana ebrbagai aktornya, organisasi, prosedur, dan teknik
yang bekerja secara bersama-sama menjalankan kebijakan tersebut untuk meraih
tujuan.
Teori Implementasi menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun
sebagaimana yang dikutip dari buku Solichin Abdul Wahab menyampaikan syarat-
syarat untuk sebuah kebijakan negara agar dapat diimplementasikan dengan
sempurna.
a) Kondisi eksternal yang dihadapai badan atau instansi pelaksana tidak akan
mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan tersebut dapat
besifat fisik, politis, atau sosial.
b) Tersedia cukup waktu dan sumber-sumber yang mencukupi untuk pelaksanaan
program.
c) Sumber-sumber yang hendak dipadukan harus benar-benar tersedia.
d) Kebijakan tersebut memiliki hubungan kausalitas yang handal.
e) Hubungan kasualitas bersifat langsung denan sedikit mata rantai
penghubungnya.
11 Bambang Sunggono. 1997. Hukum dan Kebijakan Publik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.Hlm.137
f) Hubungan saling ketergantungannya kecil.
g) Pemahaman mendalam dan ada kesepakatan bersama mencapai tujuan.
h) Tugas diperinci dan ditempatkan sesuai urutan yang tepat.
i) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
j) Pihak yang memiliki kewenangan dan kekuasaan dapat menuntut dan
mendapatkan kepatuhan yang sempurna.
Faktor pendukung implementasi kebijakan menurut George Edward III
dalam bukunya Budi Winarno sebagai berikut12:
a) Komunikasi
Tiga hal utama dalam komunikasi yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan.
Transmisi berupa kesadaran dari pejabat bahwa mengimplementasikan sebuah
keputusan yang telah dibuat adalah keharusan. Kejelasan komunikasi harus
ada, tidak hanya ketersediaan petunjuk pelaksanaan kebijakan. Konsistensi
pelaksanaan kebijakan seiring dengan implementasinya yang efektif.
b) Sumber-sumber.
Sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan adalah staf yang
memadahi serta memiliki keahlian untuk melaksanakan tugas-tugasnya,
wewenang, serta fasilitas penunang pelaksanaan pelayanan publik.
c) Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku.
Kecenderungan dari pelaksana mempunyai konsekuensi vital dalam
pelaksanaan sebuah kebijakan agar efektif. Jika perilaku pelaksana kebijakan
prima dan baik maka tujuan awal adanya kebijakan dapat tercapai.
d) Struktur birokrasi.
Birokrasi merupakan struktur pelaksana kebijakan, baik yang pemerintah
maupun badan swasta.
Buku yang sama juga menguraikan tentang factor pendukung implementasi
kebijakan oleh Van Meter dan Horn, yakni13:
a) Ukuran dan tujuan kebijakan.
Tujuan dan sasaran implementasi program dalam sebuah kebijakan harus
diidentifikasi dan terukur agar terhindarkan dari kegagalan.
b) Sumber kebijakan.
12 Budi Winarno, 2012. Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus. Jakarta: PT Buku Seru.Hlm.12613 Ibid.hlm.10
Mencakup dana atau perangsang lain yang mendorong dan mempelancar
implementasi secara efektif.
c) Komunikasi anatr organisasi dan kegiatan pelaksanaan.
Ketepatan komunikasi antar organisasi pelaksana menunjang keefektifan
imlementasi sebuah kebijakan.
d) Karakteristik badan pelaksana.
Memiliki kaitan erat dengan struktur birokrasi. Struktur birokrassi yang sehat
dan baik akan mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijkan.
e) Kondisi ekonomi, sosial , dan politik.
Mempengaruhi bdan pelaksana dalam pencapaian kebijakan tersebut.
f) Kecenderungan para pelaksana.
Intensitas kecenderungan para pelaksana kebijakan mempengaruhi proses
pelaksanaan kebijakan.
Kebijakan yang dibuat pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan
untuk internal pemerintah semata. Seluruh masyarakat dan lingkungan sekitar juga
mendapatkan dampaknya. Dorongan masyarakat untuk turut serta melaksanakan
sebuah kebijakan dari masyarakat menurut James Anderson dikarenakan14:
a) Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan badan
pemerintah.
b) Adanya kesadaran menerima kebijakan tersebut.
c) Ada keyakinan bahwa kebijakan tersebut dibuat secara sah dan konstitusional
oleh para pejabat pemerintah yang berwenang sesuai prosedur hukum.
d) Sikap menerima dan melaksanakan kebijkan sesuai dengan kepentingan
pribadinya.
e) Ada sanksi tertenu apabila tidak melaksanakan sebuah kebijakan.
Implementasi sebuah kebijakan pemerintah tak selamanya mulus tanpa
rintangan. Hambatan yang kemungkinan muncul berasal dari factor-faktor sebagai
berikut15:
a) Isi kebijakan.
Pertama, implementasi gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksud
dan tujuannya kurang terperinci, tidak ada penerapan prioritas, program
kebijakan terlalu umum. Kedua, kurangnya ketetapan intern maupun ekstern
14 Bambang Sunggono. Op.cit. hlm.14415 Ibid. hlm.149
dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan tersebut
menunjukan kekurangan yang sanagt berarti. Empat, penyebab lainnya yang
mempengaruhi kegagalan diakrenakan ada kekurangan menyangkut sumber
dayapembantu misalnya waktu, biaya, dan manusia.
b) Informasi.
Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran
yang terlibat langsung memiliki informasi yang berkaitan dengan perannya.
Informasi inilah yang justru tidak tersedia misalnya karena ada gangguan
komunikasi.
c) Dukungan.
Kesulitan pelaksanan kebijakan muncul karera tidak didukung oleh para
pelaksananya sejak awal.
d) Pembagian potensi.
Diferensiasi tugas dan wewenang organisasi yang tidak jelas berpotensi
menimbulkan masalah dalam pelaksanaan. Aspek pembagian potensi diantara
pelaku kebijakan yang tidak tegas dan tanggungjawab yang kurang disertai
pembatasaan menghambat pelaksaan kebijakan.
Kebijakan publik akan menjadi efektif bilamana dilaksanakan dam
mempunyai manfat positif bagi anggota masyarakat. Tindakan manusia sebagai
bagian dari masyarakat harus sesuai denga napa yang dikehendaki pemerintah atau
negara. Sehingga jika ada ketidaksesuaian maka suatu kebijakan menjadi tidak
akan efektif. Peraturan perundangan merupakan salah satu sarana implementasi
sebuah kebijakan publik. Berikut ini iadalah unsur yag harus dipenuhi agar suatu
kebijakan dapat terlaksana dengan maksimal16:
a) Peraturan hukum atau kebijakan itu sendiri.
Terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan antara kebijakan dengan aturan
hukum tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
b) Mentalitas petugas yang menerapakan hukum.
Petugas penegak hukum mencakup hakim, jaksa, polisi dan sebagainya wajib
memiliki mental yang positif dalam menerapkan aturan hukum. Kondisi yang
sebaliknya mengakibatkan ketimbangan atau gangguan dalam pelaksanaan isi
kebijakan.
16 Ibid, hlm.158
c) Fasilitas pendukung.
Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan peraturan hukum atau kebijakan
harus memadai sehingga pelaksanaannya dapat maksimal.
d) Warga masyarakat.
Sebagai obyek dari kebijakan perlu memiliki kesadaran hukum sebagaimana
yang dikendaki undang-undang.
F. PEMBAHASAN
1. Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia
Permasalahan anak dengan kenakalan setiap bulannya tak pernah absen
menghiasi kolom surat kabar. Kenakalan yang memberi efek pertanggungjawaban
pidana penjara tak jarang dilakukan mereka yang berusia kurang dari 18 tahun.
Dua tahun terakhir, pemerintah gencar mengedukasi aparat penegak hukum dan
masyarakat tentang sistem peradilan pidana anak yang baru. Prinsip perlindungan
dan rehabilitasi diutamakan daripada penjeraan. Sejalan dengan trend yang ada,
penulis tergelitik menelusuri sejarah hukum dari sistem peradilan pidana anak di
Indonesia. Pembatasan pembahasaan yakni rentang tahun 1900 hingga sekarang.
Sejarah peradilan anak di Indonesia di awali dari kehadiran lembaga Pro
Juventute tahun 1917. Lembaga ini digagas oleh para raja dan pemuda-pemuda di
daerah. Karena pengaruhnya yang meluas maka Kerajaan Belanda memberikan
pengakuan dan berganti nama menjadi Pra Yuwana.
Setelah kemerdekaan, para institusi penegak hukum termasuk Pra Yuwana
membuat kebijakan yang menjadi dasar perumusan sistem peradailan pidana
dikemudian hari. Yakni tahun 1954 telah terdapat hakim khusus mengadili perkara
anak yakni Mr Maengkom, menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional. Lima
tahun berikutnya terdapat consensus anatara kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan
Pra Yuwana mengenai pelaksanan pengadilan khusus untuk anak. Tindak lanjut
dari konsensus tersebut lahirlah beberapa ketentuan sebagai berikut17:
1. SEMA nonor 3 Tahun 1959 mengenai ketentuan penetapan sidang anak yag
tertutup untuk umum.
2. Kepolisian Negara juga menginstruksikan pembentukan Biro Anak-anak
atau yang kemudian digubah menjadi Polisi Urusan Anak melalui Instruksi
Menteri Kepolisian No.Pol. 17/Instruksi/1965 tanggal 23 Pebruari 1965.
17 Abintoro Prakoso. 2013. Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak. Yogyakarta: LaksbangGrafika. Hlm.34
Departemen Kehakiman melalui Direktorat Jendral Kepenjaraan mendirikan
Bimbingan Pemasyarakatan (Bispa) tahun 1968 untuk turut andil dalam menangani
anak-anak yang melanggar hukum. Bispa merupakan perubahan wajah dari Pra
Yuwana setelah ada perubahan dari Sistem Kepenjaraan menjadi Sistem
Pemasyarakatan kala Menteri Kehakiman Sahardjo18. Tujuan penempatan
narapidan di penjara adalah sebagai upaya mempersiapkan mereka kembali
kemasyarakat dengan perilaku yang lebih baik
Perkembangan global kala itu di dahului oleh PBB yang mencanangkan
Tahun Anak pada 1979 sebagai wujud peringatan 20 tahun Deklarasi Hak Anak.
PBB dan UNICEF menindaklanjuti dengan membentuk komite untuk
merumuskan konvensi hak anak. Trend internasional tersebut di sambut
pemerintah dengan positif, terlebih Indonesia merupakansebagai salah satu anggota
PBB yang aktif dalam isu anak. Pemerintah meresponnya dengan mengeluarkan
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada tanggal 23
Juli 1979. Sebagai pengingat akan pentingnya jaminan kehidupan bagi anak, maka
tanggal 23 Juli di jadikan Hari Anak Nasional. Muatan undang-undang ini
mengadopsi Deklarasi Hak Anak Internasional tahun 1959.
Hasil rumusan konvensi hak anak yang disusun sejak tahun 1979 kemudian
diadopsi oleh PBB dan dideklarasikan pada tanggal 20 November 1989 dengan
nama Convention on The Rights of The Children (CRC). Pasal 40 menekankan
tugas negara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum bahwa mereka
memiliki hak atas perlakukan yang manusiawi dan menghargai martabatnya
sebagai anak selama proses peradilan. Peningkatan perlindungan HAM bagi anak
yang berada dalam sistem peradilan memiliki banyak konsekuensi lanjutan. Produk
turunan dari CRC kemudian hadir untuk saling melegkapi. Misalnya UN Standart
Minimum Rules for the Administratio of Juvenile Justice (The Beijing Rules) nomor
40/33 tanggal 29 November 1985, UN Rules for the Protection if Juveniles
Deprived of their Liberty (Havana Rules) nomor 45/113 tanggal 14 Desember
1990, dan UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Deliquency (The Riyadh
Guidelines) nomor 45/112 tanggal 14 Desember 199019.
18 http://www.ditjenpas.go.id/sejarah. Diakses tanggal 22 Agustus 2014, pukul 10.25 WIB19 Nandang Sambas. 2013. Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen InternasionalPerlindungan Anak serta Penerapannya. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm.51
Usaha peningkatan perhatian terhadap peradilan pidana anak kian menguat.
Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang Peradilan Anak melalui
Amant Presiden Nomor R.12/PU/XII/1995. Selanjutnya DPR melakukan
pembahasaan serta diskusi yang akhirnya mengesahkan Undang-undang Nomor 3
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada tanggal 3 Januari 1997. Sebelum
undang-undang ini lahir, jumlah perkara dengan anak sebagai tersangka cukup
tinggi. Tahun 1994 terdapat 9.442 kasus, tahun 1995 terdapat 5.234 kasus, dan
1996 terdapat 4.479 kasus (Data Susenas Badan Pusat Statistik tahun 2000).
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga
memberikan perhatian terhadap peradilan pidana anak. Bab X Pasal 66
menyampaikan sebagai berikut:
(1) Setiap anak berhak tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan,
atau penjatuhan hukuman yang tidak mausiawi.
(2) Hukuman mati atau seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku
tindak pidana yang masih anak.
(3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasaanya secara
melawan hukum.
(4) Penangkapan, penahanan, atau pidana anka hanya boleh dilakukan
dengan huum yang berlaku da hanya dapat dilaksanakan secagai upaya terakhir.
(5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan
perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan
pengembangan pribadi sesuai degan usianya dan harus dipisahkan dari orang
dewasa, kecuali demi kepentingannya.
(6) Setiap anak yang dirampas kebebasaanya berhak memperoleh bantuan
hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum
yang berlaku.
(7) Setiap anak yang dirampas kebebasaanya berhak untuk membela diri
dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak
memihak dalam siding yang tertutup untuk umum.
Hak anak yang berhadapan hukum masuk menjadi point perhatian HAM.
Karena kerentanan atas pelanggaran atau pencabutan hak, mereka alami berlipat.
Ketidaktahuan masyarakat dan kelengahan pengawasan pemerintah terhadap
kinerja aparat penegak hukum memperlebar potensi pelanggaran tersebut.
Perhatian publik tersita dengan kasus persidangan RJ yang berusia 7 tahun
karena kasus perkelahian dengan temannya di Sumatera Utara. Proses persidangan
diikuti upaya penahanan oleh hakim menimbulkan reaksi besar dari pemerhati
anak. Mulai dari pelaporan hakim yang bersangkutan ke Komisi Yudisial hingga
pengajuan uji materiil di Mahkamah Konstitusi tentang batasan usia anak yang
dapat dipidanakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Putusan MK
Nomor 1/PUU-VIII/2010 menaikan batasan minimal umur anak yakni 12 tahun
yang dapat melakukan pertanggungjawaban pidana.
Kasus RJ mampu mendorong laju pembahasan revisi Undang-undang
Nomor 3 Tahun 1997 yang sekian tahun mangkrak di badan legislative.
Perlindungan bagi anak yang berhadapan hukum dianggap tidak terlalu vital jika
dibandingkan peraturan tentang investasi atau pertambangan. Pembahasaan revisi
UU Pengadilan Anak tidak mengalami kemajuan berarti. Perkembangan
masyarakat menghendaki ada suatu sistem perlindungan anak berhadapan hukum
yang komprehensif dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Kasus
kekerasaan dan dampak prisonisasi pada anak mendatangkan kerugian luar biasa.
Anak mengulangi perbuatan pidana karena mengadopsi perilaku negative dari
orang dewasa di dalam penjara. Pemenjaraan tidak terbukti efektif memperbaiki
perilaku anak.
Kembali publik terhenyak dengan kasus di Palu pada pertengahan tahun
2011, kasus anak ‘mencuri’ sandal milik seorang polisi. Hukuman penjara
mengancam sang anak yang masi berusia 15 tahun. Masyarakat membutuhkan rasa
keadilan yang tidak hanya menyentuh korban, namun juga pelaku (anak), dan
masyarakat sendiri. Pemulihan dari kerugian atas perbuatan criminal diberikan
kepada korban dan masyarakat. Sanksi yang mengedepankan pertanggungjawaban
bukan penjeraan lebih tepat bagi anak.
Stigma melekat kuat pada ABH yang telah melalui proses hukum formal.
Mereka mengalami official designation yang dapat dilihat dalam fakta birokrasi
atau aspek keperdataan. Seumur hidup mereka akan memiliki catatan criminal
dalam Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) dari kepolisian. Padahal jamak
salah satu persyaratan kerja harus mencantumkan SKKB. Unofficial designation
terasa dari sikap atau persepsi masyarakat terhadap mereka. Belum dapat menerima
kehadiran anak yang pernah bermasalah hukum20. Sanksi diluar proses peradilan
kerap terasa lebih menyakiti rasa keadilan dan HAM bagi anak-anak tersebut.
Pada tahun 2012 lahirlah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Lembaran Negara Nomor 153. Tim penyusun
berhasil memasukan prinsip keadilan restorative adopsi dari Beijing Rules yang
dipercayai lebih baik daripada undang-undang sebelumnya. Beijing Rules atau UN
Standart Minimum Rules for the Administratio of Juvenile Justice (The Beijing
Rules) nomor 40/33 mengenalkan tentang konsep keadilan restorative dan proses
diversi yang wajib diupayakan pada semua tingkatan proses hukum.
2. Keadilan Restoratif Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum
Anak adalah mereka yang berusia kurang dari 18 tahun, termasuk yang
berada di daam kandungan, sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pertumbuhan dan
perkembangan anak selalu berinteraksi dengan orang dewasa yang ada
disekitarnya. Beragam pengaruh lingkungan keluarga, pendidikan, dan sosial anak
mempengaruhi pada perilakunya.
Kecenderungan polah tingkah anak yang terekam dalam saluran pemberitaan
baik cetak maupun elektroni menunjukan peningkatan kenakalan anak dan
beragam modusnya. Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak UU SPPA), memberi pengertian anak yang
berhadapan dengan hukum (children in conflict with the law), adalah sebagai
berikut :
“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik
dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi
saksi tindak pidana”.
Romli Atmasasmita dalam buku Wagiati Soetodjo, menguraikan motivasi
intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak adalah sebagai berikut21:
a) Yang termasuk motivasi intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah :
1) Faktor intelegentia;
2) Faktor usia;
3) Faktor kelamin;
20 YesmilAnwar. 2009. Saat Menuai Kejahatan, Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi,Hukum, dan HAM. Bandung: Refika Aditama. Hlm.30821 Wagiati Soetodjo.2006. Hukum Pidana Anak. Bandung: PT Refika Aditama. Hlm. 17.
4) Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
b) Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah :
1) aktor rumah tangga;
2) Faktor pendidikan dan sekolah;
3) Faktor pergaulan anak;
4) Faktor mass media.
Berbagai faktor tersebut memungkinkan bagi anak untuk melakukan
kenakalan dan tindakan criminal. Akibat dari tindakan tersebut, mereka terpaksa
berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan. Upaya perlindungan bagi mereka
tak sebatas yang terdapat dalam UU SPPA. Sistem peradilan ini harus dimaknai
lebih luas karena juga menyentuh pada akar masalah kenakalan anak serta
pencegahannya. Lebih jauh, ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup
banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama
dengan penyidik polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial,
termasuk pelaku-pelaku dalam proses tersebut. Istilah sistem peradilan pidana anak
merujuk pada legislasi, norma dan standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan,
institusi dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan
tindak pidana22.
Pelaksanaan peraturan pidana anak yakni UU SPPA, memerlukan
seperangkan asas yang harus dipatuhi oleh pemerintah khususnya aparat penegak
hukum dan semua warga masyarakat. Asas yang dimaksud adalah sebagai
berikut23:
a) Perlindungan.
Melindungi dan mengayomi anak berhadapan hukum agar masa depannya
terjamin. Anak tetap berhak atas pembinaan untuk membangunnya sebagai
manusia berpribadi positif.
b) Keadilan.
Setiap proses penyelesaian perkara harus mencerminkan rasa keadilan bagi
anak. Penghindaran anak dari proses hukum formal dalam upaya
menyelamatkan anak dari stigmanisasi dari lingkungan sosial. Teori stigma
22 Anna Volz. 2009. Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Hukum Hak AsasiManusia Internasional. Jakarta: Yayasan Pemantau Hak Anak. Hlm.123 Abintoro Prakoso. 2013. Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak. Yogyakarta: Laksbang Grafika.Hlm.100
and seriousness menyampaikan bahwa apa yang serius bagi masyarkat maka
akan menjadi stigma yang lebih tinggi bagi orang yang melakukannya24.
c) Non diskriminasi.
Tidak adanya perlakuan yang berbeda berdasarkan suku, agama, ras,
golongan, jenis kelamin, budaya, kondisi fisik atau mental.
d) Kepentingan terbaik bagi anak.
Tindakan dan pengambilan keputusan terhadap anak menempatkan
kepentingan terbaik anak sebagai petimbangan yang utama.
e) Penghargaan terhadap pendapat anak.
Kebebasaan anak menyampaikan isi pikiran, ide, gagasan, dan harapannya
dalam pengembangan kreativitas dan daya nalarnya.
f) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
Merupakan hak asasi yang paling mendasar dan dilindungi oleh negara.
g) Pembinaan dan bimbingan bagi anak.
Peningkatan kualitas ketakwaan anak, intelektual, sikap, dan perilakunya
melalu berbagai upaya sehingga terbangun pribagi yang lebih baik.
h) Proporsional.
Perlakuan terhadapa anak harus memperhatikan batas umur dan kondisinya.
Anak berhadapan hukum berhak menerima bantuan hukum dan perlakuan
yang seimbang serta manusiawi. Prosedur hukum dijalankan memiliki potensi
menghasilkan perilaku tidak proporsional dari aparat penegak hukum. Namun
perinsip keadilan tidak dapat dikesampingkan.
i) Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir.
Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya kecuali terpaksa dan merupakan
upaya terakhir dalam upaya penyelesaian perkara.
j) Penghindaran pembalasan.
Menjauhkan upaya atau motif pembalasan dalam proses peradilan pidana
diemaban oleh semua pihak.
UU SPPA telah mengatur tentang upaya diversi yang berfungsi agar anak
yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang
harus dijalaninya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Resolusi PBB
24 Yesmil Anwar. 2009. Saat Menuai Kejahatan, Sebuah PEndekatan Sosiokultural Kriminologi,Hukum, dan HAM. Bandung: Refika Aditama. Hlm.151
tentang UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice,
(Beijing Rule) Rule 125:
“Diversion, involving removal from criminal justice processing, and
frequently redirection to community support services, is commonly practiced on a
formal and informal basis in many legal system. This practice serves to hinder the
negative effects of subsequent proceedings in juvenile justice administration (for
example the stigma of conviction and sentence). In many cases, non intervention
would be the best response. This diversion at the out set and without referral to
alternative (social) services may be the optimal response. This is especially the
case where the offence is of a non-serious nature and where the family, the school
r other informal social control institutions have already reacted, or are likely to
react, in an appropriate and constructive manner”
Konsep Diversi pertama kali dikemukakan sebagai kosakata pada laporan
peradilan anak yang disampakan Presiden Komisi Pidana (president’s crime
commissionis) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Awalnya konsep
diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai berdirinya peradilan anak (children’s
court) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan
formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (police cautioning). Prakteknya
telah berjalan di negara bagian Victoria-Australia pada tahun 1959 diikuti oleh
negara bagian Queensland tahun 1963.
Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif
terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem
peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh
kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau dalam bahasa
Indonesia diskresi. Dengan penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal yang
ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak
dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan
kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat
sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan.Setelah itu jika
ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi.
Diversi merupakan salah satu sarana memberikan keadilan restorative bagi
anak, keadilan yang bersifat memulihkan. Sebelum UU SPPA, konsep pemidanaan
25 Nandang Sambas. 2013. Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen InternasionalPerlindungan Anak serta Penerapannya. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm.61
lebih mengedepankan retributive paradigm dimana keinginan publik untuk
memidanakan anak sebagai wujud pembalasan sangat kuat. Sanksi pidana penjara
memberikan permasalahan baru bagi delinquency seperti kemerosotan
pengendalian diri, stigma berlebihan terhadap mereka, muncul ketidakpercayaan
lingkungan. Peralihan menuju restorative paradigm menjadi pilihan bijak.
Tujuan utama keadilan restorative adalah perbaikan atau penggantian
kerugian yang diderita korban, adanya pengakuan dari pelaku terhadap luka yang
dialami masyarakat karena perbuatannya. Proses rekonsiliasi annatara korban,
pelaku, dan masyarakat menjadi utama. Ketiga pihak tersebut bekerjasama
memperbaiki kehidupan bermasyarakat yang telah tercederai.
Posisi korban kerap terabaikan dalam sistem peradilan pidana karena telah
terwakili oleh jaksa. Pasal yang dituntutkan jaksa kepada pelaku kerapkali tidak
mampu menghapus kerugian yang dia alami. Tindak pidana sejatinya tidak hanya
memberi dampak pada korban, namun masyarakat juga sebagai elemen terdampak
tidak langsung. Keresahan masyarakat, rasa was-was, timbul saling tidak percaya,
merupakan wujud perilaku sosial sebagai respon tindak criminal yang terjadi
disekitarnya.
Muladi mengungkapkan cirri-ciri keadilan restorative sebagai berikut26:
a) Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain
dan dipandang sebagai konflik.
b) Fokus perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban da
kewajiban untuk masa mendatang.
c) Sifat normative diangun atas dasar dialog dan negosiasi.
d) Restitusi sebagai sarana para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan
tujuan utama.
e) Keadilan dirumuskan seabagai hubungan antar hak dan dinilai atas dasar
hasil.
f) Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan.
g) Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restorative.
h) Peran korban dan oelaku diakui dalam penentuan masalah dan
penyelesaiannya. Pelaku didorong untuk bertanggungjawab.
26 Muladi. 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: B.P. Universitas Diponegoro.Hlm.129
i) Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak atas
perbuatannya dan diarahkan untuk memutuskan yang terbaik.
j) Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh yakni moral, sosial,
dan ekonomis.
k) Stigma dapat dihapus melalui restorative.
Keadilan restorative bukan hal baru dalam kehidupan bermasayrakt. Sejak
dahulu telah berkembang metode penyelesaian permasalahan yang menggunakan
pendekatan pemulihan dengan cara konvensional. Semangat musyawarah atau
rembug adalah budaya local yang memberikan ruang para pihak (korban dan
pelaku) serat masayarakat mengambil peran seimbang dalam selesaikan masalah.
Pasal 1 angka 6 UU SPPA menyebutkan keadilan restorative sebagai
penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga
pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari
penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan
semula dan bukan pembalasan.
3. Surakarta Menuju Kota Layak Anak
Sejak 2006, pemerintah mencanangkan program Indonesia Layak Anak
(IDOLA) merujuk pada desain global dari UNICEF dan UNHABITAT yakni child
friendly cities. Program serupa dilakukan di lebih dari 100 negara di dunia. Standar
pemenuhan sebuah kota disebut layak anak (KLA) terdiri dari 31 indikator yang
merujuk pada isi Konvensi Hak Anak. Indikator tersebut terdiri dari 5 kluster
sesuai hak dasar anak sesuai Peraturan Meneg PPPA Nomor 11 Tahun 2012, yakni
1. Hak sipil dan kebebasan;
2. Kesehatan dan kesejahteraan dasar,
3. Pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya;
4. Keluarga dan pengasuhan alternatif;
5. Perlindungan khusus.
Kluster terakhir mengenai perlindungan khusus terdiri dari anak yang
membutuhkan perlindungan khusus seperti anak korban kekerasaan atau
eksploitasi, anak yang berada di situasi bencana, anak yang berhadapan dengan
hukum (ABH). Penanganan ABH dipandang penting karena publik tidak dapat
tutup mata dengan keberadaan mereka yang tersebar di hampir semua lapas/rutan
se-nusantara. Penilaian KLA tak lepas dari kesediaan data ABH dan penanganan
anak yang integratif.
Kebijakan program KLA tidak hanya ditingkat pusat, namun lebih
mendorong kabupaten/kota dan propinsi ikut menciptakan pembangunan yang
peduli pada hak, kebutuhan, dan kepentingan anak. Sinergitas program agar lebih
maksimal diwujudkan dengan melekatkan isu anak pada kementrian yang ada.
Tahun 2009 dirubahlah Kementrian Pemberdayaan Perempuan menjadi
Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan menteri
pertamanya adalah Linda Amalia Sari27.
Penghormatan hak anak oleh pemerintah kabupaten/kota dapat dilakukan
melalui beberapa cara yang direkomendasikan oleh UNICEF Innocent Research
Center28 sebagai berikut:
a. Menyediakan akses pelayanan kesehatan, pendidikan air bersih, sanitasi yang
sehat dan bebas pencemaran.
b) Menyediakan kebijakan dan anggaran khusus untuk anak.
c) Menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman sehingga memungkinkan
anak dapat berkembang, berekreasi, belajar, berinteraksi sosial, dan
melakukan ekspresi budayanya.
d) Keseimbangan di bidang sosialm ekonomi, dan terlindungi dari pengaruh
kerusakan lingkungan dan bencana alam.
e) Memberikan perhatian khusus kepada anak yang tinggal dann bekerja di jalan,
eksploitasi seksual, hidup dengan kecacatan atau tanpa dukungan orang tua.
f) Menyediakan wadah bagi anak untuk berperan serta dalam pengambilan
keputsan yang berpengaruh langsung pada kehidupan mereka.
Thomas R. Dye menjelaskan bahwa sebuah kebijakan publik dapat berate
segala sesuatu yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan oleh pemerintah.
Keduanya memiliki alasan dan akibat tertentu yang dirasakan oleh masyarakat
sebagai obyek dari kebijakan. Upaya penyediaan kebijakan berupa aturan hukum
merupakan elemen dasar dari implementasi program KLA. Kota Surakarta telah
27 http://menegpp.go.id/v2/index.php/tentangkami/kelembagaan/sejarah. Diakses tanggal 23 Agustus2014 pukul 12.20 WIB.28 Innocenti Digest. 2002. Poverty and Exclusion Among Urban Children. Florence – Italy: UNICEFInnocenti Research Centre. Edisi 2. Bulan November 2002. Hlm.22
menggagas konsep kota layak anak sejak tahun 2006. Beragam kebijakan hadir
untuk mendukung upaya tersebut seperti29 :
a) Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor 130.05/08/I/2008 tanggal 5
Pebruari 2008 tentang Tim Pelaksana Pengembangan Kota LAyak Anak
(KLA) Kota Surakarta.
b) Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor 462/74-A/I/2006 tanggal 21
Maret 2006 tentang Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta
(PTPAS). Diperbaharui melalui Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor
462.05/84-A/I/2010 tentang PTPAS.
c) Nota Kesepahaman Nomor 453/108 Tahun 2010 dalam rangka
pengembangan Kota Surakarta sebagai Kota Layak Anak. MoU ini
ditandantangani oleh pemerintah, muspika, ormas, LSM, dan lembaga
kemasayrakatan lainnya.
d) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak
Seperangkat kebijakan pemerintah memuat perlindungan dan pemenuhan
terhadap anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, salah satunya anak
yang berhadapan dengan hukum. Mereka pribadi yang masih labil dan terjerumus
pada situasi kemiskinan serta pola pengasuhan yang kurang tepat. Kadangkala
mereka pun tidak merasakan sebagai individu yang bermasalah dan tidak berusaha
menaru perawatan. Lingkungan dan institusi sosial yang berada disekitar anak-lah
yang membentuk anak menjadi demikian.
Lingkungan yang protektif bagi anak dapat digambarkan seperti lingkaran
bertingkat. Dimulai dari lingkungan terdekatnya yakni keluarga inti kemudian
kerabat atau keluarga luar (extended family). Tingkat berikutnya adalah lingkungan
masyarakat dimana anak berinteraksi misalnya lingkungan pendidikan atau sosial.
Pemerintahan dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan berjenjang
hingg atingkat pusat. Legistlatif memiliki pengaruh juga melalui produk kebijakan
yang dikeluarkannya.
Aturan hukum sebagai upaya perlindungan ABH dalam kerangka KLA perlu
ditinjau menggunakan konsep bekerjanya hukum menurut Lawrence M. Friedman
yang dikenal dengan three element of legal system30:
29 Bappeda Kota Surakarta. 2013. Percepatan Aksi Kota Layak Anak Kota Surakarta. Hlm.630 Esmi Wirasih Puji Rahayu. 2005. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. Semarang: SuryandaruUtama. Hlm.30
a) Struktur hukum.
Kelembagaan yang diciptakan sistem hukum dengan beragam fungsi dalam
rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Misalnya eksekutif,
legislative, atau yudikatif.
b) Substansi.
Output dari sebuah sistem hukum yang berwujud peraturan, keputusan yang
dapat digunakan oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
c) Kultural Hukum.
Terdiri dari nilai dan sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Kultur
hukum merupakan jembatan penghubung antara peraturan dengan tingkah
laku hukum dari warga masyarakat.
Kebijakan progam KLA bagi ABH memperhatikan perkembangan peraturan
di tingkat nasional, yakni Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Semangat keadilan restorative yang bersifat
memulihkan menjadi inti dari pelaksanaan perlindungan anak yang konflik dengan
hukum. Bukan lagi pembalasan namun mendorong pelaku anak untuk
bertanggungjawab sesuai usia dan kemampuannya.
Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS) adalah
konsorsium yang terdiri dari pemerintah, institusi penegak hukum, rumah sakit,
dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta Organisasi Kemasyarakatan
(Ormas). Lembaga yang bergabung dalam nota kesepahaman berjumlah 48 dan
terdiri dari divisi pendidikan publik, rehabilitasi dan layanan, rujukan, serta data
informasi. Koordinator PTPAS berada di bawah BAPERMAS PP PA & KB Kota
Surakarta.
Kasus kriminalitas anak menjadi wilayah garapan PTPAS juga mengingat
perspektif perlindungan anak bahwa anak dalam situasi khusus harus dilihat
sebagai korban. Setiap tahunnya tidak kurang dari 20 kasus anak melakukan
kenakalan di wilayah hukum Polresta Surakarta. Fakta tersebut mendorong
pemerintah untuk mengembangkan keberadaan PTPAS ditingkat kelurahan dengan
nama Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) sejak 2012.
PPT hadir di 51 kelurahan. Keanggotaannya terdiri dari tokoh masyarakat,
tokoh agama, wakil pemerintahan setempat, organisasi kemasyarakatan seperti
PKK, LPMK, FKPM. Fungsi layanan dan rehabilitasi berjejaring dengan PTPAS,
khususnya bagi kasus yang membutuhkan rujukan kesehatan.
Mengatasi problem ABH tidak hanya bertumpu pada norma hukum.
Dibutuhkan struktur yang terdiri dari kelembagaan dan pejabat sebagai pelaksana
tugas yang memiliki perspektif yang sama mengenai perlindungan anak. Prinsip
nondiskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak menjadi tuntutan dalam
merumuskan sebuah kebijakan.
Pendirian PPT tidak diikuti dengan penguatan struktur yang ada didalamnya
mengakibatkan fungsi layanan tidak optimal. Kelembagaan PPT terdiri dari unsur
pemerintah dan organisasi kemasyarakat di kelurahan setempat. Kapastitas
personel yang tergabung dalam PPT dalam penanganan delinquency perlu
mendapatkan dukungan dari pemerintah.
UU SPPA memberikan legalitas terhadap upaya diversi yang berkeadilan
restorative. Kebijakan ini memberikan peluang penyelewengan prosedur
dikarenakan ketidakpahaman masyarakat (PPT) dalam proses pendampingan ABH.
Budaya hukum di masyarakat yang cenderung memenjarakan anak masih kuat
terpelihara. Sehingga jumlah anak yang harus mendekam di sel kantor polisi belum
mengalami penurunan dengan adanya PPT atau PTPAS.
PPT adalah ujung tombak upaya penyelamatan masa depan ABH. Mereka
berada di lingkungan yang terdekat dengan anak sehingga (diharapkan) mengetahui
dengan jelas akar masalah anak. Partisipasi aktif PPT dalam proses diversi
merupakan hakikat tugasnya sebagai perwakilan dari masyarakat. Usulan
intervensi dalam proses mencari penyelesaian terbaik bagi perkara anak
diharapakan berimbang. Nilai edukasi dan perikemanusiaan masuk dalam rumusan
bentuk pertanggungjawaban anak sebagai pelaku. Kepentingan korban dan
masyarakat sebagai pihak yang dirugikan juga terakomodir.
G. KESIMPULAN DAN SARAN
Kota Layak Anak tidak lagi menjadi cita-cita jika pemerintah Kota Surakarta
dapat menciptakan lingkungan layak anak yang dimulai dari keluarga dan
masyarakat (kelurahan). Kerjasama antar pemerintah dan masyarakat perlu
dibangun lewat transfer informasi dan koordinasi berkala dalam wadah PPT dan
PTPAS. Peningkatan kapasitas para actor penyedia layanan berpengaruh besar
dalam proses penanganan kasus ABH. Prinsip keadilan restorative sebagaimana
amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak (UU SPPA) dapat terwujud melalui diversi yang dirintis dari bawah. Diversi
yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan masyarakat diarahkan
menuju proses pemulihan penderitaan semua pihak. Masyarakat aktif melakukan
respon terhadap kasus delinquency dengan mengutamakan kepentingan terbaik
bagi anak.
Kebijakan perlindungan terhadap anak berkonflik dengan hukum atau anak
sebagai pelaku tindak criminal tidak dapat dilakukan setengah hati. Anak sebagai
individu yang belum mandiri dan labil sangat rentan mengalami ketidakadilan.
Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan khusus melalui kebijakan-
kebijakan afirmatif. Sehingga deliquent dapat terentaskan dari akar masalah yang
menyelebungi dan mendorongnya berbuat kriminalitas. Pemerintah membangun
program yang terintegratif antar Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) karena
permasalahan anak tidak dapat diselesaikan menggunakan satu pendekatan saja.
Pejabat pemerintah harus menghindarkan sikap egosektoral karena akan
menghambat program KLA.
Dukungan anggaran daerah untuk anak tidak semata pembangunan fisik
namun mengupayakan menyentuh akar masalah dari ABH. Sehingga dibutuhkan
baseline data untuk dapat menyusun perencanaan program yang solutif dan sesuai
kebutuhan masyarakat. Program perlindungan anak yang dijalankan tidak lepas
dari proses pemantauan dan evaluasi. Tujuannya untuk mengukur tingkat
keberhasilan program dan sarana deteksi dini keefektifitasan program.
Kebijakan yang berpihak pada anak merupakan investasi jangka panjang
terhadap kualitas kehidupan sebuah bangsa. Diawali dari kebijkan tingkat kota
yang kemudian direplikasi hingga tingkat pemerintahan terkecil, adalah pilihan
bijak. Tidak cukup hanya dengan komitmen, namun langkah nyata untuk
memperbaiki kekurangan harus segera dilakukan. Tanggung jawab terhadap anak
yang berhadapan dengan hukum adalah milik bersama, pemerintah (termasuk
aparat penegak hukum) dan masyarakat.
H. DAFTAR PUSTAKA
Abintoro Prakoso. 2013. Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak. Yogyakarta:Laksbang Grafika.
Anna Volz. 2009. Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif HukumHak Asasi Manusia Internasional. Jakarta: Yayasan Pemantau Hak Anak.
Bambang Sunggono. 1997. Hukum dan Kebijakan Publik. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Bappeda Kota Surakarta. 2013. Percepatan Aksi Kota Layak Anak Kota Surakarta.Budi Winarno, 2012. Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus. Jakarta: PT
Buku Seru.C.S.T. Kansil. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta:
Balai Pustaka.Esmi Wirasih Puji Rahayu. 2005. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis.
Semarang: Suryandaru Utama.H. Abdul Manan. 2009. Aspek-aspe Perubahan Hukum. Jakarta: Kencana.H. Munir Fuady. 2003. Teori-teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum. Jakarta:
Kencana.Innocenti Digest. 2002. Poverty and Exclusion Among Urban Children. Florence –
Italy: UNICEF Innocenti Research Centre. Edisi 2. Bulan November 2002.Muladi. 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: B.P.
Universitas Diponegoro.Nandang Sambas. 2013. Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen
Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya. Yogyakarta: GrahaIlmu.
Philipe Nonet dan Philip Selznick. 2013. Hukum Responsif. Bandung: NusaMedia.
Sasmini, Diana Tantri Cahyaningsih, dan Erna Diah Kusumawati. 2013.Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Anak yang Berhadapan denganHukum yang Dititipkan di Rumah Tahanan Negada dan LembagaPemasyarakatan. Belum terpublikasi.
Satjipto Raharjo. 2010. Sosiologi Hukum. Yogyakarta/: Genta Publishing.Wagiati Soetodjo.2006. Hukum Pidana Anak. Bandung: PT Refika Aditama.YesmilAnwar. 2009. Saat Menuai Kejahatan, Sebuah Pendekatan Sosiokultural
Kriminologi, Hukum, dan HAM. Bandung: Refika Aditama. Hlm.308http://www.ditjenpas.go.id/sejarah. Diakses tanggal 22 Agustus 2014, pukul 10.25
WIBhttp://menegpp.go.id/v2/index.php/tentangkami/kelembagaan/sejarah. Diakses
tanggal 23 Agustus 2014 pukul 12.20 WIB.http://smslap.ditjenpas.go.id/public/arl/current/monthly/year/2012/month/12 .
Diakses tanggal 26 Juni 2014.