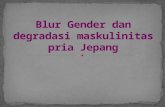kasus penolakan kopi Indonesia oleh Jepang
Transcript of kasus penolakan kopi Indonesia oleh Jepang
Kampus Tercinta – IISIP Jakarta
Institute Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta
PENERAPAN STANDAR MUTU KOPI EKSPOR INDONESIA
(Kasus Penolakan Ekspor Kopi Indonesia ke Jepang)
Nurfaridha
2012230106
PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
INSTITUT ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK JAKARTA
JAKARTA
OKTOBER 2014
DAFTAR ISI
BAB I. Pendahuluan
1.1 latar belakang
1.2 Rumusan masalah
BAB II. Kerangka Teori
2.1 Landasan teori
BAB III
3.1 Sejarah kopi
3.2 Jenis-jenis minuman kopi
3.2.1 Pemanenan dan pemisahan cangkang
3.2.2 Pemanggangan
3.2.3 Penggilingan
3.2.4 Seni perebusan
3.2.5 Dekafeinasi
3.2.6 Kafein
3.3 Sejarah kopi di Indonesia
3.4 Penolakan kopi dari Indonesia oleh Jepang
3.5 Penanganan pemerintah dalam penerapan standar mutu kopi
ekspor Indonesia
BAB IV
Kesimpulan
DAFTAR PUSTAKA
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kopi merupakan jenis tanaman perkebunan tahunan (perennial)
yang menjadi primadona bagi konsumen pasar domestik dan
international. Tanaman kopi sebagai komoditas ekspor mempunyai
nilai ekonomis relatif tinggi di pasaran dunia, dimana Indonesia
masuk dalam urutan nomor 3 penghasil kopi terbesar di dunia
setelah Brazil dan Vietnam. Dari total produksi, sekitar 67% kopi
Indonesia di ekspor sedangkan sisanya (33%) untuk memenuhi
kebutuhan dalam negeri. Beberapa jenis kopi yang paling sering di
ekspor adalah Arabika (Coffea arabica Linn), Kopi Robusta (Coffea
canephora Piere ex Froehner), Kopi Liberika (Coffea liberica Bull
ex Hien) dan Kopi Ekselsa (Coffea exelsa A. Chev). Berdasarkan
data ekspor kopi Indonesia dari tahun 2005-2011, terlihat bahwa
ekspor kopi Indonesia bergerak fluktuatif. Pada tahun 2012,
volume ekspor kopi Indonesia menunjukkan tren yang positif dengan
kenaikan volume ekspor 21,6 %. Meskipun secara volume meningkat
di tahun 2012, namun terjadi penurunan nilai ekspor kopi sebesar
24,3 % akibat harga kopi yang turun. Penurunan nilai ekspor kopi
menunjukkan bahwa harga kopi yang fluktuatif dipengaruhi oleh
musim dan persaingan kopi antar negara yang berstandar mutu.
Kementerian Pertanian RI memproyeksikan produksi kopi 2013
mencapai 763.000 ton dengan Target produksi ini naik 16,11%.
Kebutuhan kopi diperkirakan mencapai 121.107 ton per tahun dengan
Area perkebunan kopi di Indonesia seluas 1,3 juta ha, antara lain
tersebar di Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa
Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, hingga
Papua.
Ekspor kopi adalah persyaratan standar mutu yang diminta
baik oleh lembaga resmi pemerintah maupun pembeli di pasar kopi
internasional. Di dalam negeri, telah membakukan persyaratan mutu
biji kopi, begitu pula dengan Kementrian Perindustrian dan
Perdagangan yang mengeluarkan dokumentasi tentang ketentuan
ekspor kopi. Begitu pula di level internasional, masing-masing
pembeli baik firm atau country mengajukan persyaratan standar
mutu yang berbeda. Kopi berstandar mutu menjadi salah satu
komoditi pangan yang termasuk dalam kategori yang
distandardisasi. Contohnya kasus penolakan ekspor kopi Indonesia
ke Jepang, dimana Karantina Jepang menolakan 10 peti kemas berisi
200 ton kopi dari Indonesia karena melebihi batas maksimum
residu. Kopi Indonesia dianggap mengandung unsure aktif pestisida
isocarabdan carbaryl melebihi ambang batas yang diizinkan. Alasan
penolakan ini karena Jepang menetapkan batas residu carbary
sebesar 0,1 % part per bilion. Jepang menemukan kopi Indonesia
melebihi ambang batas residu herbisida antara 0,5-0,7. Penetapan
ambang batas residu Jepang atas kopi Indonesia dianggap terlalu
tinggi karena disisi lain pasar kopi ekspor ke Uni Eropa (UE)
dan Amerika Serikat (AS) menetapkan batas residu herbisida yang
lebih fleksibel yaitu hanya 0,1 Part Per Billion. Pengusaha
eksportir (Pedagang pengumpul dan industri biji kopi) dihadapkan
pada berbagai pilihan dan strategi untuk meningkatkan standar
mutu produknnya sesuai keinginan negara konsumen. Permasalahan
muncul ketika penetapan standart mutu pangan untuk komoditi kopi
ekspor, Jepang memiliki standar mutu lebih ketat dan spesifik
melalui regulasi dan berbagai persyaratan/ketentuan. Pengusaha
eksportir Indonesia, dihadapkan pada 2 pilihan, yaitu: (1) patuh
dan mengikuti regulasi standar mutu yang ditetapkan oleh
pemerintah Jepang. (2) Tidak ikut dalam standardisasi mutu Jepang
dan melakukan upaya-upaya untuk standar mutu yang disesuaikan
dengan BSN, dengan harapan Buyers Jepang akan menyesuaikan kopi
yang diinginkan sesuai dengan standar mutu milik nasional.
1.2. rumusan masalah
1. Bagaimana upaya pemerintah dalam menangani masalah
penolakan ekspor kopi Indonesia di Jepang?
BAB II
KERANGKA TEORI
2.1. Kerangka teori
Perspektif Neoliberal
Neoliberalisme dapat dikatakan telah menguasai sistem
perekonomian dunia yang mengikuti gagasan dari John Maynard
Keynes. Inti dari gagasannya menyebutkan tentang penggunaan full
employment yang dijabarkan sebagai besarnya peranan buruh dalam
pengembangan kapitalisme dan pentingnya peran serta pemerintah
dan bank sentral dalam menciptakan lapangan kerja. Beberapa
instrumen kebijakan ekonomi yang menganut paradigma
neoliberialisme, di antaranya liberalisasi, deregulasi,
privatisasi, dan pencabutan subsidi. Penerapan ketiga instrumen
itu lebih mengarah pada pemihakan yang berlebihan kepada pasar
secara konsisten. Melalui kebijakan politik negara maju dan
institusi moneter seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO, penggunaan
neoliberalisme banyak dipaksakan di berbagai negara. Bahkan,
siapa pun presiden negeri ini, kebijakan ekonominya harus market
friendly. Tidak mengherankan kalau penerapan paradigma neoliberal
hanya menguntungkan beberapa gelintir orang saja, sedangkan
sebagian besar rakyat makin terpinggirkan. Masifnya penerapan
kebijakan ekonomi dengan paradigma neoliberal tidak saja telah
menyengsarakan kehidupan rakyat kecil, tetapi juga telah merampas
kedaulatan rakyat dan mengancam kemandirian ekonomi bangsa.
Jika dikaji menggunakan prespektif Neoliberal ini, kasus
penolakan kopi Indonesia oleh Jepang dengan mutu internasional
tidak sesuai dengan konsep yang menginginkan kebebasan individu
maupun ekonomi, yang dimana menjadi teori pedoman dan acuan di
era globalisasi ini. Seharusnya jika setiap Negara memahami
konsep Neoliberal terutama dalam hal ekonomi dan perdagangan
sudah tidak ada lagi hambatan – hambatan apapun yang mewarnai
pelaksanaan perdagangan dunia, yang justru akan merugikan. Tetapi
sebagai salah satu anggota dari organisasi WTO (World Trade
Organization) Indonesia juga harus mematuhi prinsip – prinsip
yang ada pada WTO itu sendiri yaitu memberikan lebih banyak
pilihan produk dan kualitas untuk kosumen. Dengan sistem
perdagangan yang lebih global, konsumen di setiap negara dapat
mengakses produk-produk yang dihasilkan di negara lain sehingga
akan ada lebih banyak pilihan baik dari sisi produk maupun
kualitas.
BAB III
PEMBAHASAN
3.1. Sejarah kopi
Kopi adalah sejenis minuman yang berasal dari proses
pengolahan dan ekstraksi biji tanaman kopi. Kata kopi sendiri
berasal dari bahasa Arab qahwah yang berarti kekuatan, karena
pada awalnya kopi digunakan sebagai makanan berenergi tinggi.
Kata qahwah kembali mengalami perubahan menjadi kahveh yang
berasal dari bahasa Turki dan kemudian berubah lagi menjadi
koffie dalam bahasa Belanda. Penggunaan kata koffie segera diserap
ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata kopi yang dikenal saat
ini. Secara umum, terdapat dua jenis biji kopi, yaitu arabika
(kualitas terbaik) dan robusta. Ketika kopi tiba di Indonesia,
bangsa Belanda berhasil membudidayakan sekaligus menyebarkan
luaskan kopi dari perkebunan di Indonesia, terutama dari tanah
Jawa, Sumatra dan Sulawesi. Segera saja tanaman eksotis ini
menyebar ke negara-negara jajahan Eropa serta ditanam di rumah-
rumah kaca maupun perkebunan di seantero Austria dan Belanda.
Bangsa Belanda berhasil memperdagangkan kopi ke seluruh pecinta
kopi di Eropa secara lebih efisien dibanding para pedagang Arab
melalui cara menanam, memanen serta memperdagangkannya ke seluruh
pecinta kopi di dataran Eropa. Perjalanan kopi melintasi dunia ke
benua Amerika merupakan kilas balik Belanda dari perkebunan di
kepulauan Indonesia. Ketenaran kopi di Eropa pada abad 18
menjadikan kopi sebagai alat tukar maupun sebagai hadiah yang
berharga. Dari sekian banyak jenis biji kopi yang dijual di
pasaran, hanya terdapat 2 jenis varietas utama, yaitu kopi
arabika (Coffea arabica) dan robusta (Coffea robusta). Masing-masing
jenis kopi ini memiliki keunikannya masing-masing dan pasarnya
sendiri. Kopi arabika merupakan tipe kopi tradisional dengan cita
rasa terbaik. Sebagian besar kopi yang ada dibuat dengan
menggunakan biji kopi jenis ini. Kopi ini berasal dari Etiopia
dan sekarang telah dibudidayakan di berbagai belahan dunia, mulai
dari Amerika Latin, Afrika Tengah, Afrika Timur, India, dan
Indonesia. Secara umum, kopi ini tumbuh di negara-negara beriklim
tropis atau subtropis. Kopi arabika tumbuh pada ketinggian 600-
2000 m di atas permukaan laut. Tanaman ini dapat tumbuh hingga 3
meter bila kondisi lingkungannya baik. Suhu tumbuh optimalnya
adalah 18-26 oC. Biji kopi yang dihasilkan berukuran cukup kecil
dan berwarna hijau hingga merah gelap. Sedangkan kopi robusta
pertama kali ditemukan di Kongo pada tahun 1898. Kopi robusta
dapat dikatakan sebagai kopi kelas 2, karena rasanya yang lebih
pahit, sedikit asam, dan mengandung kafein dalam kadar yang jauh
lebih banyak. Selain itu, cakupan daerah tumbuh kopi robusta
lebih luas daripada kopi arabika yang harus ditumbuhkan pada
ketinggian tertentu. Kopi robusta dapat ditumbuhkan dengan
ketinggian 800 m di atas permuakaan laut. Selain itu, kopi jenis
ini lebih resisten terhadap serangan hama dan penyakit. Hal ini
menjadikan kopi robusta lebih murah. Kopi robusta banyak
ditumbuhkan di Afrika Barat, Afrika Tengah, Asia Tenggara, dan
Amerika Selatan.
3.2. Jenis-Jenis Minuman Kopi
Minuman kopi yang ada saat ini sangatlah beragam jenisnya.Masing-
masing jenis kopi yang ada memiliki proses penyajian dan
pengolahan yang unik. Berikut ini adalah beberapa contoh minuman
kopi yang umum dijumpai:
1. Kopi hitam, merupakan hasil ekstraksi langsung dari
perebusan biji kopi yang disajikan tanpa penambahan
perisa apapun.
2. Espresso, merupakan kopi yang dibuat dengan
mengekstraksi biji kopi menggunakan uap panas pada
tekanan tinggi.
3. Latte (coffee latte), merupakan sejenis kopi espresso
yang ditambahkan susu dengan rasio antara susu dan
kopi 3:1.
4. Café au lait, serupa dengan caffe latte tetapi menggunakan
campuran kopi hitam.
5. Caffè macchiato, merupakan kopi espresso yang
ditambahkan susu dengan rasio antara kopi dan susu
4:1.
6. Cappuccino, merupakan kopi dengan penambahan susu,
krim, dan serpihan cokelat.
7. Dry cappuccino, merupakan cappuccino dengan sedikit
krim dan tanpa susu.
8. Frappé, merupakan espresso yang disajikan dingin.
9. Kopi instan, berasal dari biji kopi yang dikeringkan
dan digranulasi.
10. Kopi Irlandia (irish coffee), merupakan kopi yang
dicampur dengan wiski.
11. Kopi tubruk, kopi asli Indonesia yang dibuat
dengan memasak biji kopi bersama dengan gula
12. Melya, sejenis kopi dengan penambahan bubuk
cokelat dan madu.
13. Kopi moka, serupa dengan cappuccino dan latte,
tetapi dengan penambahan sirup cokelat.
14. Oleng, kopi khas Thailand yang dimasak dengan
jagung, kacang kedelai, dan wijen.
3.2.1. Pemanenan dan Pemisahan Cangkang
Tanaman kopi selalu berdaun hijau sepanjang tahun dan berbunga
putih. Bunga ini kemudian akan menghasilkan buah yang mirip
dengan ceri terbungkus dengan cangkang yang keras. Hasil dari
pembuahan di bunga inilah yang disebut dengan biji kopi.
Pemanenan biji kopi biasanya dilakukan secara manual dengan
tangan. Pada tahap selanjutnya, biji kopi yang telah dipanen ini
akan dipisahkan cangkangnya.Terdapat dua metode yang umum
dipakai, yaitu dengan pengeringan dan penggilingan dengan mesin.
Pada kondisi daerah yang kering biasanya digunakan metode
pengeringan langsung di bawah sinar matahari. Setelah kering maka
cangkang biji kopi akan lebih mudah untuk dilepaskan. Di
Indonesia, biji kopi dikeringkan hingga kadar air tersisa hanya
30-35% Metode lainnya adalah dengan menggunkan mesin.Sebelum
digiling, biji kopi biasanya dicuci terlebih dahulu. Saat
digiling dalam mesin, biji kopi juga mengalami fermentasi
singkat. Metode penggilingan ini cenderung memberikan hasil yang
lebih baik dari pada metode pengeringan langsung.
3.2.2. Pemanggangan
Setelah dipisahkan dari cangkangnya, biji kopi telah siap untuk
masuk ke dalam proses pemanggangan. Proses ini secara langsung
dapat meningatkan cita rasa dan warna dari biji kopi. Secara
fisik, perubahan biji kopi terlihat dari pengeringan biji dan
penurunan bobot secara keseluruhan. Pori-pori di sekeliling
permukaan biji pun akan terlihat lebih jelas.Warna cokelat dari
biji kopi juga akan terlihat memekat.
3.2.3 Penggilingan
Pada tahap selanjutnya, biji kopi yang telah kering digiling
untuk memperbesar luas permukaan biji kopi. Dengan bertambah
luasnya permukaan maka ekstraksi akan menjadi lebih efisien dan
cepat.Penggilingan yang baik akan menghasilkan rasa, aroma, dan
penampilan yang baik. Hasil penggilingan ini harus segera
dimasukkan dalam wadah kedap udara agar tidak terjadi perubahan
cita rasa kopi.
3.2.4 Seni perebusan
Perebusan merupakan langkah akhir dari pengolahan biji kopi
hingga siap dikonsumsi.Untuk menciptakan minuman kopi yang
bercita rasa tinggi, perebusan biji kopi harus dilakukan dengan
baik dan sempurna.Terdapat banyak variabel dalam perebusan biji
kopi, antara lain komposisi biji kopi dan air, ukuran partikel,
suhu air yang dipakai, metode, dan waktu perebusan. Kesalahan
kecil dalam perebusan kopi dapat menyebabkan penurunan cita rasa.
Sebagai contoh, perebusan yang terlalu lama biasanya akan
menimbulkan rasa kopi yang terlalu pahit. Oleh karena itu,
bukanlah hal yang mudah untuk menyajikan kopi yang baik.
3.2.5 Dekafeinasi
Dekafeinasi atau penghilangan kafein termasuk ke dalam metode
tambahan dari keseluruhan proses pengolahan kopi. Dekafeinasi
banyak digunakan untuk mengurangi kadar kafein di dalam kopi agar
rasanya tidak terlalu pahit. Selain itu, dekafeinasi juga
digunakan untuk menekan efek samping dari aktivitas kafein di
dalam tubuh. Kopi terdekafeinasi sering dikonsumsi oleh pecandu
kopi agar tidak terjadi akumulasi kafein yang berlebihan di dalam
tubuh. Proses dekafeinasi dapat dilakukan dengan melarutkan
kafein dalam senyawa metilen klorida dan etil asetat.
3.2.6 Kafein
Kopi terkenal akan kandungan kafeinnya yang tinggi. Kafein
sendiri merupakan senyawa hasil metabolisme sekunder golongan
alkaloid dari tanaman kopi dan memiliki rasa yang pahit. Berbagai
efek kesehatan dari kopi pada umumnya terkait dengan aktivitas
kafein di dalam tubuh. Peranan utama kafein ini di dalam tubuh
adalah meningkatan kerja psikomotor sehingga tubuh tetap terjaga
dan memberikan efek fisiologis berupa peningkatan energi. Efeknya
ini biasanya baru akan terlihat beberapa jam kemudian setelah
mengonsumsi kopi. Kafein tidak hanya dapat ditemukan pada tanaman
kopi, tetapi juga terdapat pada daun teh dan biji cokelat.
Batas aman konsumsi kafein yang masuk ke dalam tubuh perharinya
adalah 100-150 mg. Dengan jumlah ini, tubuh sudah mengalami
peningkatan aktivitas yang cukup untuk membuatnya tetap terjaga.
Selama proses pembutan kopi, banyak kafein yang hilang karena
rusak ataupun larut dalam air perebusan. Di samping itu, pada
beberapa kasus pengurangan kadar kafein justru dilakukan untuk
disesuaikan dengan tingkat kesukaan konsumen terhadap rasa pahit
dari kopi. Metode yang umum dipakai untuk hal ini adalah Swiss
Water Process. Prinsip kerjanya adalah dengan menggunakan uap air
panas dan uap untuk mengekstraksi kafein dari dalam biji kopi.
Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan pada era ini juga telah
memungkinkan implementasi bioteknologi dalam proses pengurangan
kadar kafein. Cara ini dilakukan dengan menggunakan
senyawa theophylline yang dilekatkan pada bakteri untuk
menghancurkan struktur kafein.
3.3. Sejarah kopi di Indonesia
Kopi pertama kali masuk ke Indonesia tahun 1696 dari jenis
kopi Arabika. Kopi ini masuk melalui Batavia (sekarang Jakarta)
yang dibawa oleh Komandan Pasukan Belanda Adrian Van Ommen dari
Malabar - India, yang kemudian ditanam dan dikembangkan di tempat
yang sekarang dikenal dengan Pondok Kopi -Jakarta Timur, dengan
menggunakan tanah partikelir Kedaung. Sayangnya tanaman ini
kemudian mati semua oleh banjir, maka tahun 1699 didatangkan lagi
bibit-bibit baru, yang kemudian berkembang di sekitar Jakarta dan
Jawa Barat antara lain di Priangan, dan akhirnya menyebar ke
berbagai bagian dikepulauan Indonesia seperti Sumatera, Bali,
Sulawesi dan Timor. Kopi pun kemudian menjadi komoditas dagang
yang sangat diandalkan oleh VOC. Tahun 1706 Kopi Jawa diteliti
oleh Belanda di Amsterdam, yang kemudian tahun 1714 hasil
penelitian tersebut oleh Belanda diperkenalkan dan ditanam di
Jardin des Plantes oleh Raja Louis XIV. Ekspor kopi Indonesia
pertama kami dilakukan pada tahun 1711 oleh VOC, dan dalam kurun
waktu 10 tahun meningkat sampai 60 ton / tahun. Hindia Belanda
saat itu menjadi perkebunan kopi pertama di luar Arab dan
Ethiopia, yang menjadikan VOC memonopoli perdagangan kopi ini
dari tahun 1725 – 1780. Kopi Jawa saat itu sangat tekenal di
Eropa, sehingga orang-orang Eropa menyebutnya dengan “ secangkir
Jawa”. Sampai pertengahan abad ke 19 Kopi Jawa menjadi kopi
terbaik di dunia. Produksi kopi di Jawa mengalami peningkatan
yang cukup siginificant, tahun 1830 – 1834 produksi kopi Arabika
mencapai 26.600 ton, dan 30 tahun kemudian meningkat menjadi
79.600 ton dan puncaknya tahun 1880 -1884 mencapai 94.400 ton.
Selama 1 3/4 (Satu – tiga perempat) abad kopi Arabika merupakan
satu-satunya jenis kopi komersial yang ditanam di Indonesia. Tapi
kemudian perkembangan budidaya kopi Arabika di Indonesia
mengalami kemunduran hebat, dikarenakan serangan penyakit karat
daun (Hemileia vastatrix) , yang masuk ke Indonesia sejak tahun
1876. Akibatnya kopi Arabika yang dapat bertahan hidup hanya
yang berada pada ketinggian 1000 m ke atas dari permukaan laut,
dimana serangan penyakit ini tidak begitu hebat. Sisa-sisa
tanaman kopi Arabika ini masih dijumpai di dataran tinggi ijen
(Jawa Timur) , Tanah Tinggi Toraja ( Sulawesi Selatan), lereng
bagian atas Bukit Barisan ( Sumatera) seperti Mandhailing,
Lintong dan Sidikalang di Sumatera Utara dan dataran tinggi Gayo
di Nangroe Aceh Darussalam. Untuk mengatasi serangan hama karat
daun kemudian Pemerintah Belanda mendatangkan Kopi Liberika
(Coffea Liberica) ke Indonesia pada tahun 1875. Namun ternyata
jenis ini pun juga mudah diserang penyakit karat daun dan kurang
bisa diterima di pasar karena rasanya yang terlalu asam. Sisa
tanaman Liberica saat ini masih dapat dijumpai di daerah Jambi,
Jawa Tengah dan Kalimantan. Usaha selanjutnya dari Pemerintah
Belanda adalah dengan mendatangkan kopi jenis Robusta ( Coffea
Canephora) tahun 1900, yang ternyata tahan terhadap penyakit
karat daun dan memerlukan syarat tumbuh serta pemeliharaan yang
ringan , sedangkan produksinya jauh lebih tinggi. Maka kopi
Robusta menjadi cepat berkembang menggantikan jenis Arabika
khususnya di daerah – daerah dengan ketinggian di bawah 1000 m
dpl dan mulai menyebar ke seluruh daerah baik di Jawa, Sumatera
maupun ke Indonesia bagian timur. Semenjak Pemerintah Hindia
Belanda meninggalkan Indonesia, perkebunan rakyat terus tumbuh
dan berkembang, sedangkan perkebunan swasta hanya bertahan di
Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagian kecil di Sumatera; dan
perkebunan negara (PTPN) hanya tinggal di Jawa Timur dan Jawa
Tengah.
3.4. Penolakan kopi dari Indonesia oleh Jepang
Kasus penolakan biji kopi Indonesia di Jepang sebanyak 10
kontainer yang berisi 200 ton akibat melebihi batas maksimal
residu pestisida, membuat pemerintah berupaya untuk meningkatkan
kualitas kopi lokal. Kopi asal Indonesia dianggap mengandung
unsur aktif pestisida isocarab dan carbaryl melebihi ambang batas
yang diizinkan. Jepang, lanjutnya, memang termasuk negara yang
ketat dalam menerapkan standar impor produk pertaniannya termasuk
kopi Indonesia. Sejak 2006 pemerintah Jepang telah menetapkan 200
jenis bahan kimia yang tidak boleh terkandung pada komoditi kopi
melebihi ambang batas yang diizinkan, yang dikenal sebagai
uniform level sebesar 0,01 ppm. Ketentuan pemerintah Jepang ini
dinilai paling ketat dibanding negara-negara lain. Apabila pada
komoditi kopi didapati unsur aktif salah satu dari 200 jenis
bahan kimia melebihi tingkat keseragaman yang diizinkan, maka
kopi tersebut ditolak masuk ke Jepang dan harus dihancurkan atau
diekspor kembali. Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI)
memprediksi produksi kopi Indonesia baik jenis Arabica maupun
Robusta akan meningkat tahun ini. Ketua Umum AEKI Suyanto Husein
mengatakan perkembangan kopi tahun ini masih terus terjadi
seiring peningkatan permintaan dunia. Bahkan dari segi harga,
kopi Indonesia tergolong lebih mahal karena kualitasnya namun
permintaan tetap tinggi. Dia membandingkan kopi Indonesia dengan
milik Brazil. Meski tidak bisa disamakan, namun produksi kopi
Indonesia masuk dalam kategori kopi spesial dengan harga lebih
mahal. Harga kopi Brazil saat ini US$5 per kg, sedangkan kopi
Indonesia jenis arabika sudah mencapai US$8 per kg. Untuk bisa
meningkatkan produksi tahun ini, lanjutnya, dia meminta
pemerintah bersama AEKI mendorong adanya peningkatan
produktivitasnya dan pengembangan lahan. Saat ini produktivitas
lahan untuk kopi robusta 700 kg per ha dan kopi arabika 600 kg
per ha.
3.4. Penanganan pemerintah dalam penerapan standar mutu kopi
ekspor indonesia
Pemerintah memberikan perhatian serius untuk penguatan
industri kakao. Di hulu, Kementerian Pertanian memperbaki
produktivitas melalui Gerakan Kakao Nasional (Gernas) yang telah
dimulai sejak tahun 2009, yang dilengkapi dengan berbagai
kegiatan pendampingan dan pengawalan serta bantuan teknis
lainnya. Dan saat ini diperkuat lagi dengan diterbitkannya
Permentan Nomor 67 tahun 2014 yang bertujuan untuk meningkatkan
nilai tambah dan daya saing biji kakao Indonesia, mendukung
pengembangan industri berbahan baku kakao dalam negeri,
memberikan perlindungan pada konsumen dari peredaran biji kakao
yang tidak memenuhi persyaratan mutu, meningkatkan pendapatan
petani kakao, dan mempermudah penelusuran kembali kemungkinan
terjadinya penyimpangan produksi dan peredaran kakao. “Permentan
Nomor 67 tahun 2014 ini sudah melalui proses yang panjang,
diantaranya diawali adanya ketetapan Standar Nasional Indonesia
(SNI) Nomor 2323 mengenai biji kakao pada tahun 2008 dan
diperbaki di tahun 2010,” kata Menteri Pertanian RI Suswono pada
acara Gebyar Kakao Bermutu, Selasa (16/9) di Makassar. Pada
kesempatan itu, Mentan meminta komitmen dari semua pihak terkait,
lintas kementerian dan lembaga pemerintah, pemerintah daerah,
pelaku usaha agribisnis kakao, berbagai asosiasi kakao di hulu
maupun di hilir, perguruan tinggi, serta petani kakao untuk
bersama-sama mengawal kesuksesan dari implementasi Permentan
tersebut. “Secara khusus saya berpesan kepada seluruh pemerintah
daerah sentra-sentra kakao, untuk memberikan perhatian dan
dukungan dalam mempersiapkan sarana prasarana termasuk kesiapan
kelembagaan yang perlu dibangun selama masa transisi 24 bulan
ini, sebagai kesiapan untuk mengimplementasi secara efektif
Permentan tersebut pada Mei 2016 mendatang,” lanjut Mentan. Di
Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Pertanian ditugaskan sebagai mitra saudara-
saudara dalam mempersiapkan dan mengawal pelaksanaannya.
Kementerian Pertanian memposisikan peningkatan nilai tambah dan
daya saing menjadi pilar penting. Hal ini juga untuk mendukung
kebijakan hilirisasi. Dengan produk yang memiliki nilai tambah
dan daya saing diharapkan dapat menguasai pasar domestik serta
menjadi andalan sumber devisa melalui peningkatan eskpor. Capain
tersebut tentu saja tidak melupakan peran petani produsen
sehingga peningkatan kesejahteraan petani menjadi bagian penting
yang tidak terpisahkan.“Kakao merupakan komoditi strategis yang
berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Selain sebagai sumber
devisa dari ekspor, biji kakao merupakan bahan baku industri,
sumber lapangan kerja dan pendapatan masyarakat, juga berperan
dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup,” terang Mentan.
Berdasarkan publikasi FAO dan Trade Map 2013, saat ini Indonesia
tercatat sebagai produsen kakao ke-3 dunia sesudah Pantai Gading
dan Ghana. Meskipun demikian, dari segi mutu, biji kakao asal
Indonesia harus ditingkatkan, karena biji yang difermentasi masih
tergolong rendah jumlahnya, untuk memenuhi permintaan pasar yang
tinggi. Pemerintah menyatakan akan memfasilitasi peningkatan
kualitas kopi untuk tujuan ekspor, terutama ke Jepang. Hal ini
dilakukan menyusul adanya penolakan 10 peti kemas berisi 200 ton
kopi dari Indonesia yang ditolak Badan Karantina Jepang karena
melebihi batas maksimum residu beberapa waktu lalu. Kopi
Indonesia dianggap mengandung unsur aktif pestisida isocarab dan
carbaryl melebihi ambang batas yang diizinkan. Direktur Tanaman
Rempah dan Penyegar Kementerian Pertanian, Azwar Abu Bakar,
menyatakan akan mendalami kasus penolakan tersebut dan
berkonsultasi dengan pemerintah Jepang. “Ini sebenarnya bukan
ditolak, hanya kaitannya dengan beberapa kandungan yang tidak
sesuai,” (Azwar, 2012). Dia menambahkan, Jepang termasuk negara
yang ketat dalam menerapkan standar impor produk pertaniannya,
termasuk kopi Indonesia. Menurut dia, guna menanggapi kasus ini
pihaknya akan melakukan pembinaan, mulai dari produsen hingga
tingkat industri kopi untuk mencegah digunakannya unsur pestisida
melebihi batas yang diizinkan dari suatu negara. “Kami akan imbau
semua pihak terkait supaya menghasilkan suatu kualitas yang
tinggi sehingga tidak ada lagi persyaratan yang tidak terpenuhi
pada kopi.” Sejak 2006, pemerintah Jepang telah menetapkan 200
jenis bahan kimia yang tidak boleh terkandung pada komoditi kopi
melebihi ambang batas yang diizinkan. Aturan ini dikenal sebagai
uniform level sebesar 0,01 ppm. Ketentuan pemerintah Jepang ini
dinilai paling ketat dibanding negara-negara lain. Apabila pada
komoditi kopi didapati unsur aktif salah satu dari 200 jenis
bahan kimia melebihi tingkat keseragaman yang diizinkan, maka
kopi tersebut ditolak masuk ke Jepang dan harus dihancurkan atau
diekspor kembali. Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia sebelumnya
memprediksi produksi kopi Indonesia, baik jenis Arabica maupun
Robusta akan meningkat tahun ini. Produksi kopi tahun ini
ditargetkan mencapai 900 ribu ton, yang terdiri atas 180 ribu ton
Arabica dan sisanya Robusta. Tahun lalu, produksi kopi hanya
sebesar 709 ribu ton dengan rincian 155 ribu ton Arabica dan 553
ribu ton Robusta. Dari jumlah produksi itu, porsi ekspor mencapai
600 ribu ton, sedangkan sisanya untuk konsumsi domestik.
BAB IV
KESIMPULAN
Kasus penolakan biji kopi Indonesia di Jepang sebanyak 10
kontainer yang berisi 200 ton akibat melebihi batas maksimal
residu pestisida, membuat pemerintah berupaya untuk meningkatkan
kualitas kopi lokal. Kopi asal Indonesia dianggap mengandung
unsur aktif pestisida isocarab dan carbaryl melebihi ambang batas
yang diizinkan daikarenakan ketetapan standar yang diberikan oleh
Jepang terlalu ketat dan tidak sesuai dengan standar
internasional yang ditetapkan. Oleh karena itu pemerintah
Indonesia khususnya kementrian pertanian memberikan perhatian
khusus terhadap petani kakao Indonesia untuk lebih cermat dan
mengutamakan standar mutu serta kualitas kopi ekspornya serta
memahami regulasi yang berlaku disetiap Negara tujuan ekspor.
DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Steans Jill, Pettiford Llyod (2009). Hubungan internasional
prespektif dan tema (terjemahan). Yogyakarta: Penerbit Pustaka
pelajar.
Burchill, Scott. Theories of International Relationship. Pp 55-83
Fakih, Mansour. 2003.”Bebas dari Neoliberalisme”.Insist
Pers. Yogyakarta.
Jackson, Robert dan George Sorensen. “pengantar Studi
Hubungan Internasional. Halaman 139-178
Website :
http://www.pertanian.go.id/ap_posts/detil/
102/2014/09/17/09/22/07/Mentan%20Terbitkan%20Regulasi
%20untuk%20Perkuat%20Industri%20Kakao
http://industri.bisnis.com/read/20120918/99/96284/kopi-
ditolak-jepang-pemerintah-janji-bina-petani-and-industri
http://www.aeki-aice.org/index.php/id
http://www.ico.org/