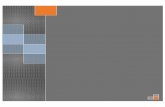Karakteristik Bahasa dan Budaya Betawi di Perkampungan ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Karakteristik Bahasa dan Budaya Betawi di Perkampungan ...
UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4 Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Pembatasan Pelindungan Pasal 26 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap: i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan
peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual; ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian
ilmu pengetahuan; iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran,
kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.
Sanksi Pelanggaran Pasal 113 1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
KARAKTERISTIK BAHASA DAN BUDAYA BETAWI
DI PERKAMPUNGAN SETU BABAKAN
Dr. Siti Gomo Attas, S.S., M.Hum.
Dr. Gres Grasia A, S.S., M.Si.
Dr. Marwiah, S.Pd., M.Pd.
KARAKTERISTIK BAHASA DAN BUDAYA BETAWI DI PERKAMPUNGAN SETU BABAKAN
Siti Gomo Attas Gres Grasia A
Marwiah
Desain Cover : Dwi Novidiantoko
Sumber : Penulis
Tata Letak :
Titis Yuliyanti
Proofreader : Windi Imaniar
Ukuran :
x, 134 hlm, Uk: 15.5x23 cm
ISBN : No ISBN
Cetakan Pertama : November 2019
Hak Cipta 2019, Pada Penulis
Isi diluar tanggung jawab percetakan
Copyright © 2019 by Deepublish Publisher All Right Reserved
Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.
PENERBIT DEEPUBLISH (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)
Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581
Telp/Faks: (0274) 4533427 Website: www.deepublish.co.id www.penerbitdeepublish.com E-mail: [email protected]
v
KATA PENGANTAR
Bismillaahirrahmaanirrahiim
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Penulis bersyukur kepada Allah SWT atas selesainya
penyusunan buku Pengantar Bahasa dan Budaya Betawi untuk
panduan mahasiswa Sastra Indonesia dan masyarakat umum. Selawat
dan salam tidak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad
SAW. Penulis merasa tertantang untuk menyelesaikan buku ini. Slogan
hidup yang selalu dipertahankan oleh penulis, yaitu banyak memberi,
menerima dan bermanfaat, seperti hadirnya buku ini diharapkan
dapat dijadikan referensi pengetahuan kepada orang banyak,
diberikan kritik untuk kesempurnaan buku ini, termasuk
kebermanfaatanya.
Perkembangan ilmu pengetahuan bahasa dan budaya terus
berkembang. Hal ini mempengaruhi pada perilaku kehidupan
masyarakat Betawi yang dianggap sebagai sebuah keniscayaan untuk
dimengerti dan dipahami. Ketersediaan sejumlah literatur ilmu bahasa
dan budaya sebagai acuan sangatlah dibutuhkan. Oleh karena itu,
buku ini disusun untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Buku ini
adalah buku tutorial sekaligus dapat digunakan untuk panduan bagi
Anda yang ingin belajar bahasa dan budaya Betawi. Buku ini ditujukan
untuk semua kalangan, baik akademisi, peneliti, dan pekerja umum
lainnya. Melalui buku ini, penulis ingin mengajak para pembaca untuk
memahami mengenai seluk beluk bahasa dan budaya Betawi.
Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan terima
kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan buku
ini. Semoga amal ibadah Bapak/Ibu selalu dirahmati oleh Allah SWT.
Pada akhirnya, penulis berharap, semoga buku ini dapat dijadikan
vi
inspirasi oleh generasi muda bangsa Indonesia untuk menjadi
generasi yang tanggap, tangguh, bermartabat, kreatif, dan mandiri.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jakarta, September 2019
Siti Gomo Attas
vii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................................v
DAFTAR ISI .......................................................................................................................... vii
BAB I PROFIL ETNIK BETAWI ........................................................... 1
A. Demografi .............................................................................................. 1
B. Asal-Usul Etnis Betawi ................................................................... 1
C. Mata Pencaharian ............................................................................. 8
D. Agama ...................................................................................................... 8
E. Kesimpulan ........................................................................................ 10
BAB II SEJARAH BAHASA BETAWI ..................................................11
A. Pengertian Bahasa Melayu Dialek Betawi ......................... 11
B. Peradaban Bahasa Melayu Dialek Betawi ......................... 11
C. Variasi Bahasa Melayu Dialek Betawi ................................. 14
D. Ciri dan Hubungan Khas Bahasa Melayu
Betawi dengan Melayu Timur.................................................. 18
E. Kesimpulan ........................................................................................ 21
BAB III MORFOSINTAKSIS BAHASA BETAWI .................................22
A. Latar Belakang ................................................................................. 22
B. Morfosintaksis Bahasa Betawi ................................................ 23
C. Pengertian Sintaksis ..................................................................... 26
D. Analisis Morfosintaksis Pantun Palang Pintu .................. 27
E. Analisis Pantun Palang Pintu ................................................... 29
F. Kesimpulan ........................................................................................ 32
BAB IV SUBDIALEK BAHASA BETAWI .............................................33
A. Latar Belakang ................................................................................. 33
B. Bahasa Betawi .................................................................................. 34
viii
C. Pengaruh Akulturasi Budaya pada Bahasa
Betawi................................................................................................... 34
D. Pembagian Wilayah Betawi ...................................................... 35
E. Perbedaan Dialek ........................................................................... 36
F. Kesimpulan ........................................................................................ 37
BAB V UNGKAPAN DAN PERIBAHASA DALAM
LENONG SKETSA KOMEDI BETAWI 'DUIT
MUTER' ..................................................................................... 38
A. Latar Belakang ................................................................................. 38
B. Bahasa Betawi .................................................................................. 38
C. Ungkapan ............................................................................................ 39
D. Peribahasa.......................................................................................... 40
E. Lenong Betawi ................................................................................. 40
F. Analisis Ungkapan dalam Lenong: Sastra
Komedi Betawi “Duit Muter” .................................................... 46
G. Ungkapan dalam Bahasa Betawi dengan
Konteksnya ........................................................................................ 46
H. Peribahasa Bahasa Betawi dan Konteksnya .................... 48
I. Kesimpulan ........................................................................................ 50
BAB VI KEPUNAHAN BAHASA BETAWI DI SRENGSENG
SAWAH ...................................................................................... 51
A. Latar Belakang ................................................................................. 51
B. Kepunahan Bahasa Betawi ........................................................ 51
C. Sosiolinguistik .................................................................................. 52
D. Bilingualisme dan Diglosia ........................................................ 52
E. Pergeseran Bahasa ........................................................................ 53
F. Pemertahanan Bahasa ................................................................. 53
G. Kepunahan Bahasa ........................................................................ 53
H. Analisis Kepunahan Bahasa Betawi di
Srengseng Sawah ............................................................................ 54
I. Kesimpulan ........................................................................................ 57
ix
BAB VII KARAKTERISTIK PERKAMPUNGAN BUDAYA
BETAWI .....................................................................................58
A. Profil Perkampungan Budaya Betawi Setu
Babakan ............................................................................................... 58
B. Implementasi Setu Babakan sebagai
Perkampungan Betawi ................................................................ 60
C. Pertunjukan Gambang Rancag ................................................ 61
D. Pertunjukan Gambang Kromong............................................ 78
E. Kesimpulan ........................................................................................ 82
BAB VIII KARAKTERISTIK PERTUNJUKAN BUDAYA
BETAWI .....................................................................................83
A. Pertunjukan Sahibul Hikayat ................................................... 83
B. Pertunjukan Lenong ..................................................................... 92
C. Pertunjukan Topeng Betawi ..................................................... 95
D. Pertunjukan Palang Pintu .......................................................... 97
E. Kesimpulan ...................................................................................... 102
BAB IX KARAKTERISTIK KULINER BETAWI ............................... 104
A. Latar Belakang ............................................................................... 104
B. Kerak Telor ...................................................................................... 105
C. Soto Betawi ...................................................................................... 107
D. Gado-Gado Betawi ....................................................................... 109
E. Bir Pletok .......................................................................................... 111
F. Kesimpulan ...................................................................................... 113
BAB X ICON BUDAYA BETAWI ...................................................... 114
A. Ondel-Ondel .................................................................................... 114
B. Bentuk/Desain ............................................................................... 114
C. Filosofi/Makna Ondel-Ondel .................................................. 115
D. Fungsi, Penggunaan dan Penempatan Ondel-
Ondel ................................................................................................... 115
E. Kembang Kelapa (Manggar) ................................................... 115
F. Ornamen Gigi Balang .................................................................. 116
G. Baju Sadariah (Sadarie) ............................................................ 117
x
H. Kebaya Kerancang .......................................................................118
I. Batik Betawi ....................................................................................119
J. Kerak Telor ......................................................................................128
K. Bir Pletok ..........................................................................................129
L. Kesimpulan ......................................................................................129
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................................131
1
PROFIL ETNIK BETAWI
A. Demografi
Masyarakat Betawi yang menempati wilayah Daerah Khusus
Ibukota Jakarta atau DKI Jakarta, menurut hasil penelitian
Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Direktorat
Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa wilayah DKI Jakarta
terhampar di dataran antara 94º45’- 94º05’ Bujur Timur dan 068’-
11º15’ Lintang Selatan memiliki daerah seluas 655 kilometer persegi
(4.5). Adapun batas-batas wilayah Jakarta adalah sebelah utara
berbatas Laut Jawa, di sebelah selatan dengan Kabupaten Bogor,
sebelah barat dengan Kabupaten Tangerang, dan sebelah timur
dengan Kabupaten Bekasi.
B. Asal-Usul Etnis Betawi
Asal mula terbentuknya etnis Betawi telah dikemukakan oleh
berbagai penelitian, baik peneliti Indonesia maupun peneliti Barat.
Salah satunya Disertasi Remco Raben yang berjudul “Batavia and
Colombo The Etnic and Sapatial, Order of Two Colonial Cieties
1600−1800” (1999, hlm. 117−157) mengemukakan bahwa asal mula
terbentuknya masyarakat Betawi, yaitu berasal dari masyarakat
pendatang. Hal ini diawali dari kemenangan Jan Pieterzoon Coen
bersama Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) (1619) merebut
Jayakarta yang pada saat itu dipimpin oleh seorang bupati yang
bernama Pangeran Jayawikarta dari Kerajaan Banten. Pasukan
Belanda yang dipimpin Jan Pieterzoon Coen berhasil merebut
Jayakarta dan mengubah namanya dari Jayakarta menjadi Batavia.
Jayakarta dihancurkan dan diubah menjadi Batavia. Pada saat itu
hampir semua penduduknya meninggalkan wilayah itu dan mereka
mengungsi ke Banten atau ke kaki Gunung Salak dan Gunung Gede.
2
Setelah kejadian itu Batavia dihuni oleh pendatang, maka kota ini pun
disebut sebagai city of migrants. Pendatang yang menghuni Batavia
ketika itu terdiri atas, (1) budak belian, (2) para pedagang Cina dan
Moor, serta Chetti (pedagang Islam dan India), (3) kelompok etnik dari
luar Jawa, dan (4) orang Jawa. Berikut adalah tabel penduduk Batavia
pada tahun 1673−1789.
Tabel 1.1 Kelompok-Kelompok Etnik di Batavia
dari Tahun 1673−1789
Tahun Ambon Bali Baljaw Bugmak Bugis Makassar Buton Mandar Sumbawa Timor
1673 303 1679 971 1689 633 15122 3861 1699 719 15649 6047 1709 414 19122 3225 1719 637 27139 4959 1729 2026 35340 7419 1739 199 31575 4521 1749 472 36254 5905 1759 307 22212 3581 2047 305 131 108 255 1969 227 1398 4274 3461 326 757 579 97 1779 449 11857 5673 6636 1830 3692 3399 2097 1789 434 30307 8203 4577 931 1406 1609 206
(Sumber: Raben 1999, hlm. 75)
Tabel tersebut menggambarkan kelompok etnik penduduk
Batavia yang berasal dari luar Jawa, selanjutnya baru pada tahun 1789
menurut catatan Raben, VOC memiliki catatan tersendiri untuk
kelompok etnik Jawa dan Sumatera.
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Melayu dan Jawa dari Tahun 1673−1789
Tahun Melayu Moojav Baljaw Jawa
1673 251 928 1679 681 798 1689 2584 15122 1699 2222 15649 1709 2169 19122 1719 3749 27139
3
Tahun Melayu Moojav Baljaw Jawa
1729 3492 35340 1739 1433 31375 1749 1952 36254 1759 1789 32385 1769 1404 35917 1779 4537 50113 1789 12318 30307
(Sumber: Raben, 1999, hlm. 75)
Kesimpulan dari kedua tabel di atas menunjukkan bahwa
kelompok etnik pribumi yang paling banyak jumlah anggotanya
tinggal di Batavia saat itu adalah pertama orang Jawa (termasuk
Banten), kedua orang Bali, dan ketiga orang Bugis Makassar. Sisanya
ditempati oleh kelompok dari Melayu dan Timor.
Berdasarkan penelitian Raben (1999) sejarah asal-usul etnis
Betawi, juga telah dibahas oleh para pakar yang mengaitkan dengan
pertumbuhan dan perkembangan penduduk kota Batavia berdasarkan
pada arsip pemerintah Kolonial Belanda. Lance Castle (1967, Edisi
Bahasa Indonesia terjemahan Gatot Triwira 2007, hlm. 10−12),
mengemukakan bahwa berdasarkan pencatatan penduduk di Batavia
tahun 1673, 1815, dan 1893 menunjukkan sejak 1673 dan 1815
jumlah penduduk dikelompokkan berdasarkan etnis. Namun, sejak
1893 menunjukkan bahwa penduduk yang berasal dari berbagai etnis
tadi kini dipresentasikan dalam satu kelompok, yaitu orang Batavia
(Betawi atau Jakarta asli). Berdasarkan informasi Raffles pada tahun
1815 sebagian penduduk Batavia itu adalah budak yang berasal dari
Bali dan Sulawesi Selatan. Berdasarkan data itu, jelas menunjukkan
bahwa suku Betawi terbentuk dari berbagai suku dan etnis Nusantara
yang mayoritas berasal dari Indonesia Timur. Di pihak lain,
kebudayaan yang turut membentuk suku baru itu, yaitu Islam dan
bahasa Melayu yang berasal dari Indonesia Barat. Jadi, dapat
dimungkinkan bahwa terbentuknya suku Betawi di Batavia saat itu
melalui proses peleburan atau melting pot.
Etnik Betawi adalah sebuah suku bangsa di Indonesia yang
penduduknya umumnya bertempat tinggal di Jakarta. Pada zaman
4
kolonial Belanda tahun 1930. Kategori orang Betawi yang sebelumnya
tidak pernah ada justru muncul sebagai kategori baru dalam sensus
penduduk tahun tersebut. Data sensus pada saat itu menunjukkan
Suku Betawi sebanyak 778.953 jiwa dan menjadi mayoritas penduduk
Batavia.
Suku Betawi menurut Jacqueline (2014) adalah sebuah suku
bangsa di Indonesia yang penduduknya umumnya bertempat tinggal
di Jakarta. Mereka adalah keturunan penduduk yang bermukim di
Batavia (nama kolonial dari Jakarta) dari sejak abad ke-17. Sejumlah
pihak berpendapat bahwa Suku Betawi berasal dari hasil perkawinan
antar etnis dan bangsa pada masa lalu. Secara biologis, mereka yang
mengaku sebagai orang Betawi adalah keturunan kaum berdarah
campuran aneka suku dan bangsa yang didatangkan oleh Belanda ke
Batavia. Apa yang disebut dengan orang atau suku Betawi sebenarnya
terhitung pendatang baru di Jakarta. Kelompok etnis ini lahir dari
perpaduan berbagai kelompok etnis lain yang sudah lebih dulu hidup
di Jakarta, seperti orang Sunda, Melayu, Jawa, Arab, Bali, Bugis,
Makassar, Ambon, dan Tionghoa. Secara etimologis kata Betawi
menurut Safitry (2014) bahwa kata ini digunakan untuk menyatakan
suku asli yang menghuni Jakarta] dan bahasa Melayu Kreol yang
digunakannya, dan juga kebudayaan Melayunya. Mengenai asal mula
kata Betawi, menurut para ahli dan sejarawan, seperti Ridwan Saidi
ada beberapa acuan:
Pitawi (bahasa Melayu Polinesia Purba) yang artinya larangan.
Perkataan ini mengacu pada kompleks bangunan yang dihormati di
Candi Batu Jaya. Sejarawan Ridwan Saidi mengaitkan bahwa
Kompleks Bangunan di Candi Batu Jaya, Tatar Pasundan, Karawang
merupakan sebuah Kota Suci yang tertutup, sementara Karawang,
merupakan Kota yang terbuka.
Betawi (Bahasa Melayu Brunei) digunakan untuk menyebut
giwang. Nama ini mengacu pada ekskavasi di Babelan, Kabupaten
Bekasi, yang banyak ditemukan giwang dari abad ke-11 M.
Flora Guling Betawi (cassia glauca), famili papilionaceae yang
merupakan jenis tanaman perdu yang kayunya bulat seperti guling
5
dan mudah diraut serta kukuh. Dahulu kala jenis batang pohon Betawi
banyak digunakan untuk pembuatan gagang senjata keris atau gagang
pisau. Tanaman guling Betawi banyak tumbuh di Nusa Kelapa dan
beberapa daerah di pulau Jawa dan Kalimantan. Sementara di Kapuas
Hulu, Kalimantan Barat, guling Betawi disebut Kayu Bekawi. Ada
perbedaan pengucapan kata "Betawi" dan "Bekawi" pada penggunaan
kosakata "k" dan "t" antara Kapuas Hulu dan Betawi Melayu,
pergeseran huruf tersebut biasa terjadi dalam bahasa Melayu.
Kemungkinan nama Betawi yang berasal dari jenis tanaman
pepohonan ada kemungkinan benar. Menurut sejarawan Ridwan Saidi
pasalnya, beberapa nama jenis flora selama ini memang digunakan
pada pemberian nama tempat atau daerah yang ada di Jakarta, seperti
Gambir, Krekot, Bintaro, Grogol dan banyak lagi. "Seperti Kecamatan
Makasar, nama ini tak ada hubungannya dengan orang Makassar,
melainkan diambil dari jenis rerumputan" Sehingga kata "Betawi"
bukanlah berasal dari kata "Batavia" (nama lama kota Jakarta pada
masa Hindia Belanda), dikarenakan nama Batavia lebih merujuk
kepada wilayah asal nenek moyang orang Belanda.
Batavia is the Latin name for the land of the Batavians during Roman times. This was roughly the area around the city of Nijmegen, Netherlands, within the Roman Empire. The remainder of this land is nowadays known as Betuwe. During the Renaissance, Dutch historians tried to promote these Batavians to the status of "forefathers" of the Dutch people. They started to call themselves Batavians, later resulting in the Batavian Republic, and took the name "Batavia" to their colonies such as the Dutch East Indies, where they renamed the city of Jayakarta to become Batavia from 1619 until about 1942, when its name was changed to Djakarta (this is the short for the former name Jayakarta, later respelt Jakarta; see: History of Jakarta). The name was also used in Suriname, where they founded Batavia, Suriname, and in the United States where they founded the city and the town of Batavia, New York. This name spread further west in the United States to such places as Batavia, Illinois, near Chicago, and Batavia, Ohio.
Kemudian penggunaan kata Betawi sebagai sebuah suku yang
pada masa hindia belanda, diawali dengan pendirian sebuah
organisasi yang bernama Pemoeda Kaoem Betawi yang lahir pada
tahun 1923.
6
Sementara itu, menurut sejarawan Sagiman MD, bahwa suku
Betawi berasal dari hasil kawin-mawin antar etnis di Batavia, ternyata
tidak sepenuhnya benar. Menurut Sagiman MD eksistensi suku Betawi
telah ada serta mendiami Jakarta dan sekitarnya sejak zaman batu
baru atau pada zaman neolitikum. Penduduk asli Betawi adalah
penduduk Nusa Jawa sebagaimana orang Sunda, Jawa, dan Madura
(Suku Betawi, 2014, http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Betawi,
diakses Kamis, 6 Agustus 2014).
Selanjutnya Arkeolog Uka Tjandarasasmita (dalam Knoerr,
2002, hlm. 203−221) menunjukkan data arkeologis bahwa “terdapat
bukti-bukti yang kuat dan ilmiah tentang sejarah penghuni Jakarta dan
sekitarnya dari masa sebelum Tarumanagara di abad ke-5.”
Dikemukakan bahwa paling tidak sejak zaman neolitikum atau batu
baru (3500–3000 tahun yang lalu) daerah Jakarta dan sekitarnya di
mana terdapat aliran-aliran sungai besar seperti Ciliwung, Cisadane,
Kali Bekasi, Citarum, pada tempat-tempat tertentu sudah didiami oleh
kelompok manusia (masyarakat). Beberapa tempat yang diyakini
berpenghuni manusia itu antara lain Cengkareng, Sunter, Cilincing,
Kebon Sirih, Tanah Abang, Rawa Belong, Sukabumi, Kebon Nanas,
Jatinegara, Cawang, Cililitan, Kramat Jati, Condet, Pasar Minggu,
Pondok Gede, Tanjung Barat, Lenteng Agung, Kelapa Dua, Cipete,
Pasar Jumat, Karang Tengah, Ciputat, Pondok Cabe, Cipayung, dan
Serpong. Jadi, menyebar hampir di seluruh wilayah Jakarta.
Berdasarkan alat-alat yang ditemukan di situs-situs itu, seperti kapak,
beliung, pahat, pacul yang sudah diumpan halus dan memakai gagang
dari kayu, disimpulkan bahwa masyarakat manusia itu sudah
mengenal pertanian (mungkin semacam perladangan) dan
peternakan. Bahkan juga mungkin telah mengenal struktur organisasi
kemasyarakatan yang teratur.
Hal senada didukung oleh Ridwan Saidi dalam pengantar JJ Rizal
pada Castle (2007, hlm. viii), Ridwan Saidi, seorang politikus dari
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) turut dalam penelitian sejarah
budaya Betawi, dengan gayanya yang khas menyebut kelompok ini
sebagai “Aliran Kali Besar” seraya mengolok-olok mereka yang getol
7
kutap-kutip Castle sebagai “orang-orang yang pada gegembolan di
bebokongnya Lance Castle” alias pengikut sejati. Menurut Ridwan
Saidi, orang Betawi berkualitas sudah ada sejak 3500 tahun yang lalu
pada zaman baru (neolitikum). Jadi, menurutnya orang Betawi itu
bukan baru muncul pada masa kolonial Belanda yang berasal dari
budak, melainkan keturunan orang mulia dari Kampung Warakas,
pendiri kerajaan Salaknegara yang diperkirakan terletak di Condet
dan berdiri pada tahun 130 M. Hal itu dikemukakan oleh Ridwan Saidi
di paparan argumennya pada pertemuan kedua narasumber ini di
depan para seniman dan pengamat Budaya Betawi di Gedung Nyi
Ageng Serang.
Siapakah orang Betawi dan dari mana asalnya—pendek kata
sejarahnya orang Betawi mesti dicarikan jawaban. Memang kualitas
tak jatuh dari keturunan, tetapi pertanyaan sejarah itu bukan berarti
mesti diremehkan dan tidak harus dicari jawabannya. Sebisanya mesti
dijawab, sebab itu menyangkut sejauh mana sebetulnya kita
bersungguh-sungguh dengan sejarah. Sejarah yang lebih adil, yang
bisa menjadi sumber inspirasi dan pedoman yang menuntun
masyarakat pendukungnya sekarang belajar serta mengetahui serta
mengerti seraya bekerja keras untuk mencapai arah ke mana mereka
mesti menuju.
Dalam konteks itu saling silang tentang sejarah asal usul orang
Betawi menjadi penting dan perlu disyukuri sebagai tanda bahwa arah
mencari sejarah yang adil tengah berjalan, dan di sana sejarah sebagai
gambaran masa lalu yang adalah pula merupakan berita pikiran atau
discourse yang menuntut adanya proses dialogis telah terjadi dan
tinggal kini orang Betawi mengambil hikmahnya dari setiap
historiografi atau penulisan sejarah yang terlibat dalam polemik itu
untuk menjawab keprihatinan dan kegelisahan sosial−kultural mereka
yang harus bertanggung jawab memajukan kehidupan manusia
Betawi sekaligus manusia Indonesia.
Sebutan suku, orang, dan kaum Betawi, menurut laporan van
der Aa (1846 dalam Shahab, 2004, hlm. 4 dan Chaer, 2012, hlm. 6)
muncul dan mulai populer ketika Mohammad Husni Tamrin
8
mendirikan perkumpulan "Persatoean Kaoem Betawi" pada tahun
1923 dan ikut serta dalam semangat Sumpah Pemuda dan Kongres
Pemuda II tahun 1928. Meski ketika itu penduduk asli belum
dinamakan Betawi, tapi Kota Batavia disebut "negeri" Betawi sebagai
kategori "suku" dimunculkan dalam sensus penduduk tahun 1930.
C. Mata Pencaharian
Mata pencaharian orang Betawi dapat dibedakan antara yang
berdiam di tengah kota dan yang tinggal di pinggiran. Di daerah
pinggiran sebagian besar adalah petani buah-buahan, petani sawah,
dan pemelihara ikan. Namun, makin lama areal pertanian mereka
makin menyempit, karena makin banyak yang dijual untuk
pembangunan perumahan, industri, dan lain-lain. Akhirnya para
petani ini pun mulai beralih pekerjaan menjadi buruh, pedagang, dan
lain-lain.
D. Agama
Agama yang dianut oleh penduduk DKI Jakarta beragam.
Menurut data pemerintah DKI pada tahun 2005, komposisi penganut
agama di kota ini adalah Islam (84,4%), Kristen Protestan (6,2 %),
Katolik (5,7 %), Hindu (1,2 %), dan Buddha (3,5 %). Jumlah umat
Buddha terlihat lebih banyak karena umat Konghucu juga ikut
tercakup di dalamnya. Angka ini tidak jauh berbeda dengan keadaan
pada tahun 1980, di mana umat Islam berjumlah 84,4%; diikuti oleh
Protestan (6,3%), Katolik (2,9%), Hindu dan Buddha (5,7%), serta
tidak beragama (0,3%). Menurut Cribb, pada tahun 1971 penganut
agama Konghucu secara relatif adalah 1,7%. Pada tahun 1980 dan
2005, sensus penduduk tidak mencatat agama yang dianut selain
keenam agama yang diakui pemerintah.
Berbagai tempat peribadatan agama-agama dunia dapat
dijumpai di Jakarta. Masjid dan musala, sebagai rumah ibadah umat
Islam, tersebar di seluruh penjuru kota, bahkan hampir di setiap
lingkungan. Masjid terbesar adalah masjid nasional, yaitu Masjid
Istiqlal yang terletak di Gambir. Sejumlah masjid penting lain adalah
9
Masjid Agung Al-Azhar di Kebayoran Baru, Masjid At-Tin di Taman
Mini, dan Masjid Sunda Kelapa di Menteng.
Sedangkan gereja besar yang terdapat di Jakarta antara lain,
Gereja Katedral Jakarta, Gereja Santa Theresia di Menteng, dan Gereja
Santo Yakobus di Kelapa Gading untuk umat Katolik. Masih dalam
lingkungan di dekatnya, terdapat bangunan Gereja Immanuel yang
terletak di seberang Stasiun Gambir bagi umat Kristen Protestan.
Selain itu, ada Gereja Koinonia di Jatinegara, Gereja Sion di Jakarta
Kota, Gereja Kristen Toraja di Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Bagi umat Hindu yang bermukim di Jakarta dan sekitarnya,
terdapat Pura Adhitya Jaya yang berlokasi di Rawamangun, Jakarta
Timur dan Pura Segara di Cilincing, Jakarta Utara. Rumah ibadah umat
Buddha antara lain Vihara Dhammacakka Jaya di Sunter, Vihara
Theravada Buddha Sasana di Kelapa Gading, dan Vihara Silaparamitha
di Cipinang Jaya. Sedangkan bagi penganut Konghucu terdapat
Kelenteng Jin Tek Yin. Jakarta juga memiliki satu sinagoge yang
digunakan oleh pekerja asing Yahudi.
Masalah pengaruh agama Islam bagi orang Betawi sangat kuat.
Berdasarkan sejarah, menurut Aziz (2002, hlm. v) tercermin pada
identifikasi mereka terhadap Islam yang menyebabkan anggota
komunitas yang tidak beragama Islam dipandang bukan bagian
komunitas etnis dari orang Betawi.
Persoalan identifikasi orang Betawi Islam di wilayah Indonesia
bukanlah kasus khas, dalam arti masih ada komunitas etnis lain di
Nusantara yang juga mengalami hal yang sama, seperti komunitas
etnis Melayu Riau, atau Batak Mandailing di Tapanuli Selatan. Namun
tentu proses identifikasi masing-masing etnis terhadap Islam sudah
pasti berbeda antara yang satu dengan yang lain disebabkan oleh
perbedaan konteks budaya.
Kehadiran orang Betawi dan kemampuannya untuk bertahan
hidup di tengah kekuasaan semacam itu tampaknya mempunyai
kaitan erat bukan semata-mata dengan unsur-unsur kebudayaan
seperti bahasa atau kesenian, tetapi justru dengan faktor Islam.
Dengan kata lain, ketahanan hidup orang Betawi sebagai sebuah
komunitas etnis berkaitan erat dengan proses Islamisasi mereka.
10
Menurut Aziz (2002, hlm. 4) dan Saidi (1997, hlm. 171−197)
agama Islam bagi orang Betawi tampil sebagai salah satu simbol
pembeda yang sangat penting dalam menghadapi penetrasi kekuatan
luar. Terdapat banyak petunjuk historis, bahwa di masa lalu ketaatan
orang Betawi terhadap syariat Islam tidaklah terlalu kuat. Namun,
Islam telah memberi orang Betawi identitas pembeda dengan
komunitas lain, sehingga sebelum istilah Betawi lazim digunakan,
mereka (orang Betawi) menyebut diri mereka dengan Orang Selam.
Termasuk banyak perlawanan fisik orang Betawi dilakukan dengan
menggunakan simbol-simbol Islam.
Bentuk identitas orang Betawi dengan agama Islamnya sudah
dibuktikan dengan bentuk isolasi yang mereka lakukan terhadap
kebudayaan modern yang diperkenalkan penjajah Belanda. Salah satu
bentuk penolakan mereka, terutama di masa penjajahan, untuk
menerima dan mengembangkan sistem pendidikan (sekolah) modern.
Dibanding suku lain yang kelak banyak menyumbang bagi
pembentukan lapisan elite Indonesia sebagai hasil pendidikan
modern, hanya sedikit orang Betawi yang mau memanfaatkan
kehadiran sekolah yang sebagian didirikan justru di kota mereka
sendiri.
E. Kesimpulan
Profil budaya Betawi adalah mengenai gambaran masyarakat
Betawi yang menempati wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau
DKI Jakarta dengan berbagai karakter yang dimiliki. Karakter budaya
Betawi akan terlihat dalam kehidupan masyarakat Betawi seperti cara
hidup dalam keseharian, bekerja, beragama, dan berkesenian.
11
SEJARAH BAHASA BETAWI
A. Pengertian Bahasa Melayu Dialek Betawi
Pengertian Bahasa Melayu dialek Betawi Menurut C.D. Grijns
(1991) pada dasarnya bukanlah bahasa (language) tapi suatu bentuk
(dialect) dari bahasa Melayu. Abdul Chaer sependapat dengan
pendapat C.D. Grijns lebih memilih untuk meluluhkan identitas bahasa
Betawi menjadi bahasa Melayu dialek Jakarta (1976). Pandangan lain
tentang bahasa Betawi menurut Saidi (1993) bahwa bahasa Betawi
adalah bahasa yang yang diadopsi dari bahasa Kawi, termasuk Melayu,
Arab, Portugis, Cina, belanda melebihi bahasa Melayu sendiri.
Sementara Muhadjir berpendapat sama dengan Grijns dan
Chaer. bahwa bahasa yang ada di Jakarta bukanlah bahasa Jakarta atau
Betawi. Bahasa Melayu Dialek Betawi yang dipakai masyarakat Jakarta
memiliki ciri penanda kosa kata. Berdasarkan hasil penelitian
Swadesh yang dikemukakan oleh Muhadjir (2018) dalam Seminar
Pelacakan Peradaban di Jakarta menunjukkan bahwa penanda kosa
kata bahasa menunjukkan sebagian besar berasal dari bahasa
Indonesia sebanyak 93%. Sementara penanda kosa kata bahasa
Betawi hanya 7%, yang berasal dari kosa kata bahasa Jawa, Sunda,
cina, dan Bali. Jadi secara linguistik dari hasil penelitian menunjukkan
bahwa bahasa Betawi adalah bahasa Melayu dialek Betawi.
B. Peradaban Bahasa Melayu Dialek Betawi
Istilah peradaban dalam Encyclopedia Britannica (1974) sering
digunakan sebagai persamaan yang lebih luas dari istilah budaya yang
populer dalam kalangan akademis. Di mana setiap manusia dapat
berpartisipasi dalam sebuah budaya, yang dapat diartikan sebagai
seni, adat istiadat, kebiasaan, kepercayaan, nilai bahan perilaku dan
kebiasaan dalam tradisi yang merupakan sebuah cara hidup
masyarakat. Sementara dalam definisi yang lain peradaban juga
12
sebagai cara sebagai normatif, baik dalam konteks sosial di mana
rumit dan budaya kota dianggap unggul lain “ganas” atau “biaab”
budaya, konsep dari peradaban dipakai konsep dari peradaban
digunakan sebagai sinonim untuk “budaya”. Peradaban juga dapat
diartikan sebagai puncak pencapaian. Untuk pencapaian peradaban
itu ada tiga indikator, yaitu sistem pemerintahan, sistem ekonomi, dan
IPTEK.
Khusus untuk peradaban bahasa Melayu Dialek Betawi juga
dapat dikatakan sebagai sebuah peradaban yang dimiliki oleh suatu
suku atau etnik yang dinamakan Jakarta. Jakarta atau Betawi memiliki
ciri penanda sebagai dialek atau bentuk bahasa Melayu yang dipakai
untuk berkomunikasi secara lisan dan tulis dalam sebuah ikatan
budaya dan wilayah yaitu budaya Betawi yang ada di Jakarta dan
sekitar Jakarta. Peradaban Bahasa Melayu dialek Betawi atau Jakarta
dimulai ketika bahasa Melayu sudah mulai dipakai di Jakarta, ketika
masih bernama Sunda Kelapa. Sebagai kota pelabuhan dan
perdagangan, Sunda Kelapa mempunyai hubungan yang luas dengan
berbagai kota pelabuhan lain di Nusantara. Pada saat itu, ada dugaan
bahwa selain bahasa Sunda, penduduknya juga sudah menggunakan
bahasa Melayu sebagai lingua franca khususnya dalam melakukan
hubungan perdagangan. Menurut catatan Grijns (1991:1) bahwa satu-
satunya bahasa Melayu tertua yang dipakai dalam bahasa lisan abad
ke-17 adalah bahasa Melayu.
Temuan penggunaan bahasa Melayu pada abad ke-17 di Kalapa
oleh Grijns tersebut masih belum cukup sebagai bukti yang kuat untuk
menunjukkan sudah adanya penggunaan bahasa Melayu pada masa
itu. Barulah ketika masa kekuasaan VOC di Jakarta, saat itu bernama
Batavia dan beberapa wilayah di Indonesia telah ditemukan berupa
dokumen-dokumen resmi, berupa surat menyurat, surat-surat
perjanjian, dan sebagainya yang ditujukan kepada penguasa-penguasa
di daerah-daerah di seluruh kekuasaannya ditulis dalam bahasa
Belanda yang disertai terjemahan dalam bahasa Melayu (Muhadjir,
2005: 60).
13
Bahasa Melayu yang dipakai di dalam dokumen-dokumen
tersebut tidak tertulis siapa penerjemah bahasa tersebut. Namun
berdasarkan pelacakan dari bentuk tulisannya memiliki ciri-ciri yang
sama dengan contoh yang terdapat dalam bahasa Melayu yang dipakai
di Batavia. Bahasa yang dipakai dalam karya sastra tulis itu memiliki
ciri bahasa Melayu yang sama pula seperti bahasa Melayu dalam surat
kabar berbahasa Melayu yang terbit sekitar tahun 1850-an di Batavia
yang juga menggunakan bahasa Melayu dialek Betawi. Contoh awal
bahasa koran Melayu tulis Betawi di hari kemudian sejajar dengan
yang dikenalnya mesin cetak huruf latin. Sejarah menunjukkan bahwa
setelah hadir mesin cetak huruf latin, maka dimulai pula dengan
suburnya bermunculan sastra tulis berbahasa Melayu cetak latin yang
juga memiliki ciri yang sama dengan penggunaan bahasa Melayu
Betawi (Muhadjir, 2005: 61).
Hasil riset dari Yayah B. Lumintang (1980), C.D. Grijns (1983)
dan Muhadjir (1979) dalam pernyataan Abdul Chaer (2018) pada
acara peluncuran Buku Pantun Betawi Zainuddin al Batawi di Setu
Babakan bahwa sebagian imigran baru yang datang ke Jakarta, mereka
meninggalkan bahasa asalnya dan menggunakan bahasa Betawi
modern (menurut bahasa Betawi modern (menurut nama yang
diberikan Wallace) sebagai bahasa pergaulan sehari-hari mereka.
Kondisi ini menunjukkan keberadaan masyarakat asli Jakarta
dibentuk oleh pendatang dan masyarakat asli. Selanjutnya mereka
bergabung menjadi masyarakat metropolitan Jakarta dengan bahasa
Melayu Jakarta sebagai komunikasinya.
Dilanjutkan oleh Abdul Chaer (2018) bahwa kedatangan orang
dari luar Jakarta pada awalnya, datang dan membawa bahasa asalnya.
Namun pada saat mereka berkomunikasi sesama pendatang misalnya,
Bali, Flores, Bugis, Ambon dan lain-lain mereka langsung
menggunakan bahasa Melayu yang dipakai oleh penduduk setempat
yang disebut “omong Jakarta”. Begitu juga apa yang disampaikan oleh
Ningsi dan Purwaningsih (2008: 497-499) bahwa dalam kalangan
remaja yang kuliah di Jakarta akan menggunakan bahasa Melayu
dialek Betawi sebagai alat komunikasi dengan lingkungan bahasanya,
14
baik formal atau informal. Bahasa ini akan dipakai dalam situasi
percakapan di lingkungan kampus dengan setting kegiatan akademik
lainnya. Sementara ranah informal digunakan saat mahasiswa yang
bersangkutan berkomunikasi dengan teman kampus, misalnya
‘ngobrol”, bercanda, dan pada saat mereka membahas sesuatu yang
sifatnya santai.
C. Variasi Bahasa Melayu Dialek Betawi
Ciri paling menonjol pada bahasa Melayu dialek Betawi dari
Bahasa Melayu lainnya adalah ciri tata ucapannya. Bahasa Melayu
dialek Betawi mempunyai aspek khas yang berbeda dengan Melayu
Klasik. Misalnya kata dalam bahasa Melayu umumnya berakhiran
vokal ‘a’ dalam Bahasa Melayu dialek Betawi menjadi “e”. Berikut ada
beberapa aspek ciri Bahasa Melayu dialek Betawi.
1. Ciri Fonologi
Tabel 2.1. Akhiran Vokal
Bahasa Melayu Klasik Bahasa Melayu dialek Betawi Apa Gula
Mangga Tua Saya
Ape’ Gule’
Mangge’ Tue’ Saye’
(Sumber Muhadjir, dkk. 1986)
Selain ciri akhiran vokal di atas, dialek dalam bahasa Melayu
dialek Betawi secara fonologi juga ditandai dengan ketikhadiran dari
konsonan “h” pada suatu kata, terutama pada bahasa Melayu Klasik
diakhiri dengan “h”.
Tabel 2.2. Akhiran Konsonan Menjadi Vokal
Bahasa Melayu Klasik Bahasa Melayu dialek Betawi Dua puluh
Tujuh Subuh
Duapulu Tuju Subu
15
Bahasa Melayu Klasik Bahasa Melayu dialek Betawi Pilih
Boleh Pilih Bole
(Sumber Muhadjir, dkk. 1986)
Hal yang lain ditunjukkan adanya kata-kata dalam bahasa
Melayu Klasik diakhiri dengan “h” dan dilafalkan sebagai vokal, dalam
bahasa Melayu dialek Betawi dilafalkan dengan “e”.
Tabel 2.3. Akhiran Konsonan Menjadi Vokal
Bahasa Melayu Klasik Bahasa Melayu dialek Betawi Abdullah
Darah Merah
Sebelah Kalah Susah
Dulle’ Dare’ Mere’
Sebele” Kale’ Suse”
(Sumber Muhadjir, dkk. 1986)
2. Ciri Morfologi
Secara morfologi bahasa Melayu dialek Betawi juga dipengaruhi
oleh bahasa Bali terutama dalam akhiran ‘”in”. Sementara pengaruh
bahasa Sunda juga terdapat pada akhiran “an”, sebagai berikut.
Tabel 2.4. Akhiran “in” Pengaruh bahasa Bali
Bahasa Melayu Klasik Bahasa Melayu Dialek Betawi
Pengaruh Bahasa Bali Ambilkan
Tolong Mengikuti
Ambilin Tulungin Ngikutin
(Sumber Muhadjir, dkk. 1986)
Contoh di atas adalah ciri morfologi juga Bahasa Melayu dialek
Betawi yang dipengaruhi oleh bahasa Bali terutama dalam akhiran
“in”. Tabel 5 di bawah ini juga bagaimana bahasa Melayu dialek Betawi
yang dipengaruhi oleh bahasa Sunda.
16
Tabel 2.5. Akhiran “an” Pengaruh bahasa Sunda
Bahasa Melayu Klasik Bahasa Melayu Dialek Betawi
Pengaruh Bahasa Sunda Lebih besar
Lebih murah Lebih baik
gedean murahan baekan
(Sumber Muhadjir, dkk. 1986)
Sementara dalam bahasa Indonesia terdapat dua akhiran -i dan -
kan. Dalam bahasa Betawi hanya terdapat satu akhiran saja, yaitu –in.
Kata-kata Indonesia mendatangi, menyembunyikan, mengambilkan,
menjahitkan, dalam bahasa Betawi adalah: ndatangin, ngumpetin,
mgambilin, dan ngejaitin. Akhiran –an, sama bentuknya dengan
bahasa Indonesia atau bahasa Melayu lain, tetapi penggunaannya di
Jakarta cukup khas. Dalam bahasa Betawi akhiran itu bisa menyatakan
‘lebih’ bila dihubungkan dengan bentuk dasar adjektiva, seperti
cepetan, tinggian, baikan, ‘lebih cepat’, ‘lebih tinggi’, ‘lebih baik’, dan
sebagainya. Akhiran –an juga sering hadir pada kata-kata yang dalam
bahasa Indonesia tanpa akhiran itu, seperti nggak bakalan ‘tidak
akan’, (apa-)-apaan ‘apakah’, nggak karuan 'tidak karuan’, gedongan
‘rumah gedong’. Awalan maen dan keje’ Frasa kata kerja dengan maen
tampaknya juga khas Betawi seperti terdapat dalam maen pukul, maen
ambil, maen tubruk dan sebagainya, yang berarti ‘melakukan
pekerjaan secara sembarangan, semaunya sendiri’.
Model pembentukan kata itu juga terdapat dengan ‘awalan’ kejè
atau kerja (pinggiran) seperti terdapat dalam kejè ketawa ‘membuat
orang ketawa’, kejè mare ‘menyebabkan kemarahan’, kejè nangis
‘menyebabkan tangis’, dan sebagainya. Jadi semacam awalan
pengubahan kata kerja intransitif menjadi transitif. Bentuk itu seperti
pembentukan transitif kata kerja bahasa Melayu Ambon yang
menggunakan kata kasi dengan sangat produktif sebagai pembentuk
kata kerja transitif, seperti pada Melayu Ambon: (1) dia kasi mandi dia
punya anak ‘ia memandikan anaknya’. (2) Hasan ada kasi panas itu
rotan ‘Hasan memanaskan rotan itu’.
17
3. Ciri Sintaktis
a. Ciri yang Bersifat Tata Kalimat
Ciri yang bersifat tata kalimat, khususnya menonjol dengan
munculnya berbagai kata partikel kalimat seperti si(h), kek,
dong, deh, dan sebagainya, seperti pada:
a) Lu udè nggak kenal langgar sih.
‘Kau tidak lagi mengenal Musalla’
b) Tapinyè bilang dulu amè si Miun dong yè
‘Tetapi bicarakan dulu dengan si Miun, ya’
c) Nyai kek, perawan sini kek
‘(Tidak peduli), apakah nyai atau gadis dari sini’
d) Belon pulang kok delmannyè ada di blakang.
‘Dia belum pulang, mengapa delmannya sudah ada di
belakang’.
b. Ciri Sintaksis Lain
Ciri sintaksis lain ialah (a) frasa milik yang dinyatakan
dengan punya di antara dua kata dalam frase nomina yang
‘memiliki’ dan ‘yang dimiliki’. seperti Amat punya rumah untuk
‘rumah amat’, saya punya bini ‘istri saya’. (b) Urutan frase
penunjuk itu dan ini berurutan terbalik dengan bahasa
Indonesia seperti ini rumah, atau itu anak, dan sebagainya.
4. Kosa Kata
Daftar Kosa kata Bahasa Betawi Menurut Asalnya
BAHASA ASAL JUMLAH Jawa 897= 18.37 %
Sunda 22 = 8,64% Jawa-sunda 1076= 22.005%
Melayu 1719= 35.21% Lain-lain 768= 15.73%
Daftar kosa kata ini Swadesh (Muhadjir, 2005) ini menurut Kosa
kata bahasa Betawi terdapat jumlah yang sama banyaknya dengan
18
bahasa asalnya, terdapat kata yang terdapat baik dalam bahasa Sunda
maupun bahasa Jawa sebanyak 1076 atau 22.05%, yang sama dengan
bahasa Sunda 22 kata atau 8.64% dan dengan bahasa jawa 897 atau
18.37%. Selebihnya sama dengan kosa kata dari bahasa Arab, Cina,
Belanda, Portugis, dan bahasa dari Timur lainnya.
D. Ciri dan Hubungan Khas Bahasa Melayu Betawi dengan
Melayu Timur
Ciri khas Betawi bidang morfologi dan ciri sintaksis (a) dan (b)
merupakan ciri Bahasa Melayu di sebelah timur Indonesia, seperti
Ambon, Manado, dan beberapa bahasa Melayu di Nusa Tenggara. Di
Manado orang mengatakan dia punya istri, dengan de pe istri (de = dia,
pe= punya, dan di Ambon orang menggunakan kata pung untuk fungsi
yang sama. (c) awalan verba dengan kata kasi, buat atau keje adalah
sejajar dengan awalan verba transitif kausatif kasi seperti, kasik
kaburun, kasi tahu ibumu bahwa, dan sebagainya.
Lokasi tempat bahasa Melayu Betawi di Ibukota RI ternyata
membawa ‘nasib baik’, melebihi peran bahasa Melayu lokal lainnya.
Kedudukan Jakarta sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, ekonomi,
dan kebudayaan nasional, mengakibatkan mudahnya tersebarnya
Bahasa etnisnya ke seluruh wilayah RI, bahkan ke dunia internasional.
Penduduk dari wilayah lain, khususnya anak-anak muda, dan lebih
spesial para PRT, yang setiap tahun pulang mudik, bukan saja
membawa oleh-oleh barang impor, tetapi juga model pakaiannya,
rambutnya, dan dikampungnya dengan bangga mengucapkan dua tiga
kata baru dari ibu kota, dong, lu, gue, cewek-cowok dan sebagainya. Di
pihak lain, staf kedutaan besar di luar negeri, umumnya datang dari
Jakarta, sehingga ketika kita berkunjung ke kedutaan besar RI,
khususnya dalam kunjungan santai seperti halalbilhalal, dan upacara
tujuh belas Agustusan, terasa seperti di Jakarta dengan Bahasa atau
logat Bahasa Indonesia santai.
Belum lagi kalau kita bicara peran media masa, khususnya radio
dan televisi dengan acara tayang wicaranya, pertunjukan seni
sandiwara dan filmnya, melaluinya kata-kata khas Betawi hadir dan
19
tersebar. Bahasa Indonesia informal seperti wawancara, iklan, dan
sebagainya, bahkan merambah ke situasi pembicaraan formal pun
unsur Betawi sering dipakai untuk mencairkan situasi yang terlalu
tegang. Dengan kata lain Bahasa Betawi dalam percakapan Bahasa
Indonesia dipilih sebagai variasi Bahasa Indonesia informal. Ketika
orang ingin melakukan alih kode untuk meredakan ketegangan, untuk
mengakrabkan mitra tutur, mungkin juga untuk memperjelas masalah
yang sulit, mengambil unsur Betawi. Singkatnya Bahasa Betawi ke
depan akan merupakan bahasa Indonesia informal.
Gambar 1. Kata-Kata dalam Bahasa di Dunia
Setelah membaca buku ‘Glosari Betawi’ (Ridwan Saidi) dan
‘Kamus Dialek Jakarta’ (Abdul Chaer) terlihat para pakar pun memiliki
pandangan berbeda mengenai bahasa Betawi. Menurut peneliti
Belanda C.D. Grijns, ‘bahasa Betawi’ pada dasarnya bukanlah bahasa
(language), tapi suatu bentuk dialek (dialect) dari bahasa Melayu.
Kamus tulisan Abdul Chaer lebih memilih peluluhan identitas bahasa
Betawi menjadi bahasa Melayu dialek Jakarta. Sedangkan Saidi
memiliki pandangan berbeda karena menurutnya orang Betawi sudah
ditemukan sebelum orang Eropa tiba di Batavia (Nusa Kalapa) dan
lingua franca Jawa dan Madura adalah bahasa Kawi, bukan Melayu.
Dalam perbendaharaan bahasa Betawi banyak kosa kata dari
bahasa Kawi. Ditambah lagi dengan perbendaharaan bahasa Melayu,
20
Arab, Portugis, Cina, Belanda melebih bahasa Melayu sendiri. Di
sekolah kita diajarkan lingua franca Nusantara adalah bahasa Melayu.
Dan sepintas bahasa Betawi itu hanyalah bahasa Indonesia (Melayu)
dengan menggantikan bunyi vokal ‘a’ di akhir kata menjadi bunyi ‘e’
(mis. ‘buka’ menjadi ‘buke’). Dari peristiwa tersebut, ada beberapa
penambahan unsur budaya dan serapan bahasa lain sehingga boleh
masuk dalam definisi pertama ‘dialek’ Melayu. Di sini saya bisa
mengerti posisi Abdul Chaer.
Namun, pemikiran saya lebih condong kepada pemikiran Saidi.
Menurut salah satu definisi bahasawan, ‘dialek’ suatu bahasa adalah
jika pengguna dialek tersebut dapat berbicara dengan pengguna
bahasa utama tanpa kesalahpahaman. Dengan kata lain, bahasa
Betawi hanyalah dialek Melayu jika orang Betawi berbicara dengan
orang Melayu tanpa ada salah pengertian. Selain sulit, saya bayangkan
eksperimen di atas dapat menghasilkan hiburan yang patut menjadi
ide sinetron komedi.
Sinetron Indonesia memang sangat populer di negara-negara
berbahasa Melayu seperti Malaysia, Singapura dan Brunei. Jika kita
bertemu dengan jiran, mereka pun bangga menceritakan bahwa
mereka ‘seronok’ mengikuti sinetron dan lagu-lagu Indonesia. Mereka
dapat mengerti (sebagian besar) Bahasa Indonesia lalu mengapa kita
tidak menyebut Bahasa Indonesia sebagai dialek Melayu?
Definisi bahasawan kedua untuk ‘dialek’ biasanya memiliki
konotasi negatif sebagai bahasa informal, lisan, tidak terdokumentasi
atau bahasa ‘slang’. Ditambah dengan pengaruh sosio-kultural,
nasionalisme dan politik, yang seharusnya di dalam kategori ‘dialek’,
justru menjadi ‘bahasa’. Selain contoh Bahasa Indonesia dan Bahasa
Melayu, di Eropa pun terjadi yang sama. Bahasa Belanda tidak disebut
‘Bahasa Jerman Dialek Belanda’ padahal bahasa Belanda masuk dalam
rumpun bahasa Jerman.
Contoh yang lebih dekat adalah bahasa Minangkabau yang juga
mengalami perdebatan yang sama namun tidak disebut ‘Bahasa
Melayu Dialek Minangkabau’. Terlebih lagi banyak etnis Melayu di
daerah penggunaan bahasa Minangkabau. Karena hingga detik ini para
21
bahasawan pun belum memiliki kesepakatan mengenai definisi
‘dialek’, saya lebih memilih sebutan ‘bahasa Betawi’ sebagai bahasa
terpisah dan bukan ‘bahasa Melayu Dialek Betawi’, apalagi dialek
Jakarta. Selain alasan yang saya paparkan di atas, mungkin etnisisme
saya sedikit mempengaruhi pendirian saya. Namun etnisisme ini yang
mungkin menjadi pendorong kelangsungan hidup bahasa Betawi dan
bahasa-bahasa lain di Indonesia.
E. Kesimpulan
Bahasa dan budaya Betawi akan terlihat dalam bentuk bahasa
dialek Betawi yang digunakan sejak masa pemerintahan Belanda.
Bahwa masyarakat Betawi telah melepaskan bahasa daerah mereka
ketika tinggal di Jakarta terutama dalam pergaulan. Bahasa Betawi
khususnya akan tergambar dalam bentuk surat kabar dan berbagai
arsip pemerintahan umumnya telah menggunakan bahasa Melayu
dialek Betawi. Penciri bahasa dialek Betawi ini akan terlihat pada
sistem morfologi dan sintaksis bahasa dialek Betawi dengan
penggunaannya di masyarakat. Bahasa Melayu dialek Betawi lebih
dikenal dengan omong Jakarta. Bahasa betawi ini juga tergambar
dalam karya sastra Betawi seperti naskah yang ada di betawi. Naskah
ini dikembangkan oleh keluarga Muhammad Bakir. Bahasa dialek
Betawi tergambar dalam bahasa naskah Pecenongan terutama
mengangkat cerita-cerita wayang dengan ciri khas bahasa Betawi.
Karya sastra yang lain yaitu dalam sahibul hikayat bagaimana penutur
hikayat membawakan hikayat dengan cara yang unik dan mencirikan
bahasa dialek Betawi. Karya sastra yang lain adalah Gambang Rancag
adalah tuturan yang diiringi lagu dengan music gambang kromong.
Lagu-lagu yang dibawakan dengan cerita tokoh yang dibawakan
adalah berciri bahasa dialek Betawi. Termasuk cerita dalam sastra
cetak si Doel anak Sekolahan membawakan cerita yang khas karakter
dan ciri bahasa Betawi.
22
MORFOSINTAKSIS BAHASA BETAWI
A. Latar Belakang
Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Betawi di Jakarta
memiliki keunikan tersendiri. Etnik Betawi merupakan percampuran
dari beberapa etnik seperti Bugis, Hindu, Cina, Melayu, Arab, Belanda,
serta Portugis. Hal tersebut yang menjadikan kebudayaan Betawi
menjadi beragam. Masyarakat Betawi sangat menghargai para
pendatang. Misalnya setiap ada acara-acara dari etnik lain selalu
diundang dan dianjurkan untuk memakai adat daerah mereka sendiri.
Selain itu, kearifan lokal warga Betawi yang selalu mencari solusi
dengan cara yang elegan, kuat rasa humor tanpa harus kehilangan
substansi, dirasakan sebagai sebuah kekuatan yang harus
dipertahankan.
Selain itu, masyarakat Betawi dikenal dengan masyarakat
egaliter atau terbuka. Masyarakat betawi sendiri tidak memiliki strata
atau tingkatan-tingkatan. Hal tersebut terbukti melalui bahasanya
yang setara. Tidak seperti bahasa Jawa yang memiliki strata bahasa
atau tingkatan. Meskipun bahasa Betawi tidak mengenal tingkatan,
namun memiliki dialek yang tersebar di beberapa daerah di wilayah
Ibu Kota dan sekitarnya. Contohnya, di daerah Condet memiliki dialek
Betawi yang berbeda dengan daerah Tanah Abang.
Hakikat Bahasa Betawi atau Melayu Dialek Jakarta atau Melayu
Batavia (bew) adalah sebuah bahasa yang merupakan anak bahasa
dari Melayu. Mereka yang menggunakan bahasa ini dinamakan orang
Betawi. Bahasa ini hampir seusia dengan nama daerah tempat bahasa
ini dikembangkan, yaitu Jakarta. Pengertian lain dari bahasa Betawi
adalah bahasa kreol (Siregar, 2005) yang didasarkan pada bahasa
Melayu Pasar ditambah dengan unsur-unsur bahasa Sunda, bahasa
Bali, bahasa dari Cina Selatan (terutama bahasa Hokkian), bahasa
Arab, serta bahasa dari Eropa, terutama bahasa Belanda dan bahasa
23
Portugis. Bahasa ini pada awalnya dipakai oleh kalangan masyarakat
menengah ke bawah pada masa-masa awal perkembangan Jakarta.
Komunitas budak serta pedagang yang paling sering menggunakan-
nya. Karena berkembang secara alami, tidak ada struktur baku yang
jelas dari bahasa ini yang membedakannya dari bahasa Melayu,
meskipun ada beberapa unsur linguistik penciri yang dapat dipakai,
misalnya dari peluruhan awalan me-, penggunaan akhiran –in
(pengaruh bahasa Bali), serta peralihan bunyi /a/ terbuka di akhir
kata menjadi /e/ atau /є/ pada beberapa dialek lokal.
Berdasarkan penjelasan tersebut, karya tulis ini disusun untuk
meneliti morfosintaksis bahasa Betawi yang terdapat dalam Pantun
Palang Pintu. Palang pintu Merupakan bagian dari salah satu
rangkaian upacara adat pernikahan Betawi yang menggunakan seni
berbalas pantun. Pantun yang digunakan merupakan salah satu dari
keanekaragaman sastra lisan yang bisa ditranskripsi dalam bentuk
tulisan. Transkripsi pantun pada palang pintu itulah yang dijadikan
objek pada penelitian karya tulis ini untuk mengetahui morfosintaksis
dalam bahasa Betawi terlebih dahulu perlu kita ketahui pengertian
morfosintaksis dan penerapan morfosintaksis dalam analisis Pantun
Palang Pintu Betawi.
B. Morfosintaksis Bahasa Betawi
Jika kita ingin mengetahui bahasa Betawi lebih dalam sebainya
kita memahami Morfologi bahasa betawi. Secara etimologi, kata
morfologi berasal dari kata morf yang berarti bentuk dan kata logos
yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah kata morfologi berarti ilmu
mengenai bentuk. Di dalam kajian linguistik, morfologi berarti ilmu
mengenai bentuk-bentuk dan pembentukan kata (Chaer, 2008).
Berdasarkan pendapat di atas, penulis menarik kesimpulan
bahwa morfologi adalah bagian dari struktur bahasa yang
mempelajari struktur dan pembentukan kata-kata serta aturan-aturan
pembentukan kata tersebut. Ciri bahasa Betawi yang menonjol dalam
bidang morfologi adalah:
24
a) Awalan Kata Kerja Prenasal
Tabel prefiks me-(nasal) dalam kata kerja
Kata kerja dasar dalam bahasa
Indonesia
Prefiks me-(nasal) dalam bahasa
Indonesia
Prefiks me-(nasal) dalam bahasa Betawi
Pukul memukul mukul Bakar membakar mbakar
Kunyah mengunyah ngunye Ganggu mengganggu ngganggu
Untuk bentuk-bentuk dasar yang mulai dengan /b/, /d/, /j/,
atau /g/ bervariasi dengan bentuk nge- (nge-bakar); (nge-jahit); (nge-
dabrek); (nge-ganggu).
b) Awalan ber-
Bentuk awalan ini mempunyai ciri khas. Hampir dalam semua
bentuk dasar tidak pernah muncul utuh ber-, melainkan hanya bentuk
be-. Namun yang paling sering, awalan ini tidak diucapkan, khususnya
yang bentuk dasarnya kata kerja.
Tabel sufiks –in dalam kata kerja
Kata kerja dalam bahasa Indonesia
Prefiks ber- dalam bahasa Indonesia
Prefiks ber- dalam bahasa Betawi
Bisik berbisik bebisik Janji berjanji bejanji Karat berkarat bekarat Jalan berjalan bejalan Temu bertemu betemu
c) Akhiran –in
Dalam bahasa Betawi hanya terdapat satu akhiran saja, yaitu
–in.
25
Tabel sufiks –in dalam kata kerja
Kata kerja dalam bahasa Indonesia
Akhiran –i / -kan dalam bahasa Indonesia
Akhiran –in dalam bahasa Betawi
Datang mendatangi ndatangin Sembunyi menyembunyikan ngumpetin
Jahit menjahitkan ngejaitin Ambil mengambilkan ngambilin
d) Akhiran –an
Akhiran –an sama bentuknya dengan bahasa Indonesia atau
bahasa Melayu lain. Tetapi penggunaannya di Jakarta, cukup khas
dalam bahasa Betawi akhiran tersebut bisa menyatakan lebih bila
dihubungkan dengan bentuk dasar adjektiva.
Tabel sufiks –an dalam adjektiva
Adjektiva dasar Akhiran –an dalam
bahasa Betawi Arti
Tinggi tinggian lebih tinggi Cepat cepatan lebih cepat Baik baikan lebih baik
e) Bentuk Kata Ulang
Dalam bahasa Indonesia terdapat dua bentuk ulangan kata yaitu
(1) ulangan kata penuh seperti laki-laki dan sebagainya; (2) ulangan
kata awal seperti lelaki atau tetangga. Dalam bahasa Betawi, terdapat
lebih banyak jenis ulangan kata yang ke-2 seperti tetamu (tamu),
gegares (makan), bebenah (merapi-rapikan), gegaruk (garuk-garuk),
sesengukan (tersengguk-sengguk).
f) Awalan maén dan kejé
Frasa kata dengan maén tampaknya merupakan khas bahasa
Betawi, contohnya maen pukul, maen ambil, maen tubruk, dan
sebagainya. Maen di sini berarti “melakukan sesuatu secara
sembarangan atau semaunya sendiri”. Model pembentukan kata itu
juga terdapat pada awalan kejé /kəjє/ (kerja/menjadikan/mmbuat)
contohnya kejé ketawa (membuat orang tertawa), kejé mare
26
(membuat orang marah), kejé nangis (membuat orang menangis) dan
sebagainya.
C. Pengertian Sintaksis
Ilmu sintaksis atau ilmu tata kalimat adalah salah satu cabang
linguistik yang membicarakan konstruksi frasa klausa, dan kalimat.
Sintaksis menyelidiki semua hubungan antar kata atau antar frasa
dalam satuan dasar sintaksis atau kalimat (Verhaar 1982: 70).
Menurut Ramlan, sintaksis adalah bagian atau cabang ilmu bahasa
yang membicarakan seluk beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa.
(1981: 1).
Dapat disimpulkan bahwa sintaksis merupakan ilmu yang
berhubungan dengan pola-pola dan aturan gramatikal yang
membicarakan seluk beluk kata, frasa, klausa, dan kalimat yang
digunakan sebagai sarana menyusun dan menggabungkan kata-kata
untuk membentuk suatu satuan bahasa.
Ciri sintaksis yang menonjol dari bahasa Betawi terdapat dalam
munculnya berbagai partikel pada suatu klausa atau kalimat, seperti
sih, kek, dong, dan sebagainya.
“Lu ude nggak kenal langgar sih.” (kau tidak lagi mengenal
musala)
“Tapinye bilang dulu ame si Miun, dong ye!” (tetapi bicarakan
dahulu dengan si Miun, ya)
Dua ciri lain dalam sintaksis bahasa Betawi adalah (1) frasa
kepemilikan dinyatakan dengan kata punya (mempunyai) seperti
Amat punya rumah, aye punya bini; (2) posisi kelas kata determinan
berbalikan dari bahasa Indonesia, contohnya ini rumah (rumah ini),
itu anak (anak itu). Jadi, pengertian Morfosintaksis yaitu bagian dari
tata bahasa Betawi yang menjelaskan mengenai ilmu morfem dan ilmu
kalimat yang digunakan oleh masyarakat betawi sebagai pengguna
bahasa melayu dialek betawi
27
D. Analisis Morfosintaksis Pantun Palang Pintu
Analisis morfosintaksis akan lebih jelas jika kita menggunakan
bahasa melayu dialek betawi dalam berbagai komunikasi salah satu
media komunikasi bahasa dialek betawi dapat ditunjukkan melalui
tuturan dalam tradisi lisan betawi yang disebut pantun palang pintu.
Berikut ini adalah bentuk palang pintu yang akan dianalisis dengan
morfosintaksis.
Pantun Palang Pintu di Daerah Condet
P = pemain dari pihak calon pengantin perempuan
L = pemain dari pihak calon pengantin laki-laki
P : Eh, bang, bang. Berenti, bang! Budeg ape lu? Eh bang, nih ape
maksudnye nih selong-selonong di kampung orang, emangnye lu
kagak tau kalo nih kampung ade yang punye?
Eh bang,
Rumah gedongan rumah belande
pagarnye kawat tiangnye besi
gue kagak mao tau nih rombongan datengnye dari mane mau ke
mane
tapi lewat kampung gue kudu permisi.
L : Oh, jadi lewat kampung sini kudu permisi, bang?
P : Iye. Emangnye lu kate ini tegalan?
L : Maapin aye bang, kalo kedatangan aye ama ni rombongan
kagak berkenan di ati sodare-sodare. Sebelomnye aye pengen
ucapin dulu nih, bang. Assalamualaikum.
P : Alaikumsalam.
L : Begini bang,
makan sekuteng di pasar jumat
mampir dulu di kramatjati
aye dateng ama rombongan dengan segala hormat
mohon diterime dengan senang ati.
P : Oh, jadi elu ude niat dateng ke mari? Eh, bang,
kalo makan buah kenari
28
jangan ditelen bijinye
kalo lu ude niat ke mari
gue pengen tau ape hajatnye.
L : Oh, jadi abang pengen tau ape hajatnye? Emang abang kagak
dikasih tau ame tuan rumenye, bang?
ade siang ade malem
ade bulan ade matahari
kalo bukan lantaran perawan yang di dalem
kagak bakalan nih laki gue anterin ke mari.
P : Oh, jadi lataran perawan, abang ke mari? Eh bang,
kagak salah abang beli lemari
tapi sayang kagak ade kuncinye
kagak salah abang dateng ke mari
tapi sayang tuh perawan ude ade yang punye.
L : Oh, jadi tuh perawan ude ade yang punye? Eh bang,
crukcuk kuburan cine
kuburan islam aye yang ngajiin
biar kate tuh perawan ude ade yang punye
tetap aje nih laki bakal jadiin.
P : Oh, jadi elu kagak ngarti pengen jadiin? Eh bang,
kalo jalan lewat kemayoran
ati-ati jalannye licin
daripada niat lu kagak kesampean
lu pilih mati ape lu batalin?
L : Oh, jadi abang bersikeras, nih? Eh bang,
ibarat baju udah kepalang basah
masak nasi udah jadi bubur
biar kate aye mati berkalang tanah
setapak kagak nantinye aye bakal mundur.
P : Oh, jadi lu sangke kagak mau mundur?
ikan belut mati ditusuk
dalam kuali kudu masaknye
eh nih palang pintu kagak ijinin lu masuk
sebelum lu penuin persyaratannye.
29
L : Oh, jadi kalo mao dapet perawan sini ade syaratnye, bang?
P : ade, jadi pelayan aje ade syaratnye, apalagi perawan.
L : Kalo begitu, sebutin syaratnye, bang!
P : Lu pengen tau ape syaratnye?
kuda lumping dari tangerang
kedipin kate cari menantu
pasang kuping lu terang-terang
adepin dulu jagoan gue satu persatu!
L : Oh, jadi kalo mao dapet perawan sini syaratnye berkelai ni,
bang?
P : Iye, kalo lu takut, lu balik gi dah!
L : Bintang seawan-awan
aye itungin beribu satu
berape banyak abang punye jagoan
aye bakal adepin atu-atu!
E. Analisis Pantun Palang Pintu
Analisis palang pintu menggunakan morfosintaksis akan
dianalisis sebagai berikut.
1. Penggalan : Eh, bang, bang. Berenti, bang! Budeg ape lu? Eh
bang, nih ape maksudnye nih selong-selonong di
kampung orang, emangnye lu kagak tau kalo nih
kampung ade yang punye?
Eh bang,
Rumah gedongan rumah belande
pagarnye kawat tiangnye besi
gue kagak mao tau nih rombongan datengnye
dari mane mau ke mane
tapi lewat kampung gue kudu permisi.
Analisis : Dalam bahasa Betawi, prefiks ber- kebanyakan
konsonan /r/ tidak dibaca jelas sehingga
terdengar berenti.
30
Nih kampung = kampung ini; nih rombongan =
rombongan ini. Dalam bahasa Betawi, posisi
determinan dengan kata yang diterangkan itu
terbalik dari kaidah bahasa Indonesia.
2. Penggalan : Maapin aye bang, kalo kedatangan aye ama ni
rombongan kagak berkenan di ati sodare-sodare.
Sebelomnye aye pengen ucapin dulu nih, bang.
Assalamualaikum.
Analisis : Maapin, ucapin adalah morfem bahasa Betawi
yang sufiksnya menggunakan akhiran –in
menggantikan sufiks –i dan –kan dalam bahasa
Indonesia.
3. Penggalan : Oh, jadi abang pengen tau ape hajatnye? Emang
abang kagak dikasih tau ame tuan rumenye,
bang?
ade siang ade malem
ade bulan ade matahari
kalo bukan lantaran perawan yang di dalem
kaga bakalan nih laki gue anterin ke mari.
Analisis : Susunan sintaksis kaga bakalan nih laki gue
anterin ke mari, terdapat klausa yang bertukar
posisi dari saya tidak akan mengantar laki-laki ini
ke sini. Salah satu ciri khas sintaksis bahasa
Betawi adalah susunan kalimat atau klausa yang
berbeda dari bahasa Indonesia.
Bakalan merupakan adverbia +an yang
merupakan ciri bahasa Betawi untuk bersifat
menegaskan. Contoh lainnya seperti beloman,
udahan. Adapun beberapa kata nomina +an
menjadi kata kerja, dan kata adjektiva +an
berfungsi memberikan keterangan “lebih”.
4. Penggalan : Oh, jadi tuh perawan ude ade yang punye? Eh
bang,
crukcuk kuburan cine
31
kuburan islam aye yang ngajiin
biar kate tuh perawan ude ade yang punye
tetap aje nih laki bakal jadiin.
Analisis : Ngajiin berasal dari kata mengajikan
(membacakan kitab suci untuk). Prefiks me-
(nasal) yang sering dipakai dalam bahasa Betawi
adalah hilangnya me dengan nasal yang masih
tertinggal sesuai konsonan pertamanya (kaji-
mengaji-ngaji). Sedangkan sufiks –in sebagai
pengganti –kan dalam bahasa Indonesia.
5. Penggalan : Oh, jadi elu kagak ngarti pengen jadiin? Eh bang,
kalo jalan lewat kemayoran
ati-ati jalannye licin
daripada niat lu kagak kesampean
lu pilih mati ape lu batalin?
Analisis : Ngarti/ngerti (mengerti) merupakan ciri khas
morfologi pada bahasa Betawi di mana
menghilangkan prefiks me dengan nasal yang
tetap pada kata kerja dasar.
Kesampean (tersampaikan) adalah morfologi
bahasa Betawi di mana prefiks ter- berubah
menjadi ke- namun tetap dalam posisi kata kerja,
dan sufiks –kan berubah menjadi –an (tetap kata
kerja).
6. Penggalan: : Oh, jadi abang bersikeras, nih? Eh bang,
ibarat baju udah kepalang basah
masak nasi udah jadi bubur
biar kate aye mati berkalang tanah.
Analisis: : Nih merupakan partikel yang berfungsi
menegaskan kalimat sebelumnya yang biasa
digunakan dalam bahasa Betawi.
7. Penggalan: : Lu pengen tau ape syaratnye?
kuda lumping dari tangerang
kedipin kate cari menantu
32
pasang kuping lu terang-terang
adepin dulu jagoan gue satu persatu!
Analisis : Bahasa Betawi juga terdapat ulangan kata
sebagian. Menantu merupakan kata ulang
sebagian.
F. Kesimpulan
Secara umum, dapat dipahami bahwa bahasa Betawi yang kita
kenal merupakan bahasa Melayu dialek Betawi. Dalam hal pengaruh,
bahasa Betawi mendapat bantuan dari berbagai bahasa mulai dari
Arab, Cina, Melayu, Eropa, Sunda, dan Jawa. Dalam lingkup geografis,
dialek Betawi terbagi menjadi dua yaitu Betawi Tengahan dan
Pinggiran. Betawi Tengah melingkupi daerah perkampungan Betawi
di sekitar Jakarta Kota, Sawah Besar, Tugu, Cilincing, Kemayoran,
Senen, Kramat, hingga batas paling selatan di Meester (Jatinegara).
Sementara itu, Betawi Pinggir melingkupi Jatinegara ke Selatan,
Jagakarsa, Depok, Rawa Belong, Ciputat hingga ke pinggir selatan
hingga Jawa Barat. Ada beberapa perbedaan ciri antara dialek Betawi
Tengah dan Pinggir, seperti ciri vokal akhir é tidak berlaku bagi
bahasa Melayu Betawi dialek Pinggiran. Kedua, sejajar dengan itu,
konsonan h yang terdapat dalam akhir kata, di dialek pinggiran tetap
sama seperti dalam bahasa Indonesia.
Bahasa Betawi merupakan salah satu karakteristik masyarakat
Betawi yang bersifat egaliter. Bahasa Betawi yang di gunakan dalam
pertunjukan palang pintu dapat dianalisis dari segi morfosintaksis,
karena palang pintu merupakan seni berbalas pantun dengan
menggunakan bahasa Betawi sehari-hari. Analisis morfosintaksis
meliputi kajian morfologi dan sintaksis yang mana menjelaskan
tentang kaidah dan struktur morfologi dan sintaksis dalam tuturan
pertunjukan berbalas pantun di masyarakat betawi sebagai ciri dan
karakteristik budaya betawi.
33
SUBDIALEK BAHASA BETAWI
A. Latar Belakang
Etnis Betawi adalah sebuah suku bangsa di Indonesia yang
penduduknya umumnya bertempat tinggal di Jakarta. pada zaman
kolonial Belanda tahun 1930, kategori orang Betawi yang sebelumnya
tidak pernah ada justru muncul sebagai kategori baru dalam data
sensus tahun tersebut. Jumlah orang Betawi sebanyak 778.953 jiwa
menjadi mayoritas penduduk Batavia waktu.
Lance Castles dalam penelitiannya mengenai penduduk Jakarta
di mana jurnal penelitiannya diterbitkan tahun 1967 oleh Cornell
University yang mengatakan bahwa secara biologis mereka yang
mengaku sebagai orang Betawi adalah keturunan kaum berdarah
campuran aneka suku dan bangsa yang didatangkan oleh Belanda ke
Batavia. Kelompok etnis ini lahir dari perpaduan berbagai kelompok
etnis yang ada di Indonesia (Sunda, Melayu, Jawa, Bali, Bugis,
Makassar, dan Ambon) maupun dari luar negeri seperti Arab, India,
Tionghoa, dan Eropa.
Penelitian yang dilakukan oleh Lance Castles tersebut
menitikberatkan pada 4 sketsa sejarah yaitu: Daghregister, catatan
harian tahun 1673 yang dibuat Belanda yang berdiam di kota benteng
Batavia; catatan Thomas Stamford Raffles dalam history of Java pada
tahun 1815; catatan penduduk pada Encyclopaedia van Nederlandsch
India tahun 1893; sensus penduduk yang dibuat pemerintah Hindia
Belanda pada tahun 1930.
Menurut Muhadjir (2000: 12), secara geografis masyarakat
Betawi terbagi menjadi dua yaitu Betawi Tengah/kota dan Betawi
Pinggir/kota. Pembagian ini ditandai dengan penggunaan bahasa yang
kemudian disebut dengan sub dialek bahasa Betawi. Adanya beragam
pengaruh yang membuat pembagian ini lantas akan dibahas lebih
lanjut dalam karya tulis ini.
34
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui letak geografis yang
mempengaruhi dialek bahasa Betawi, bagaimana perbedaan bahasa
Betawi serta untuk memahami sub dialek Betawi. Untuk mengetahui
sub dialek bahasa betawi alangkah baiknya kita terlebih dahulu
memahami pengertian bahasa betawi, Pengaruh Akulturasi Budaya
pada Bahasa Betawi, Pembagian Wilayah Betawi, dan Perbedaan
Dialek. Berikut akan dijelaskan hal yang mempengaruhi sub dialek
bahasa Betawi
B. Bahasa Betawi
Bahasa Betawi yang dikenal merupakan bahasa Melayu dialek
Betawi. Pada mulanya bahasa Betawi digunakan oleh masyarakat
menengah ke bawah. Bahasa
Bahasa Betawi
Bahasa Indonesia Bahasa Betawi
Bahasa Indonesia
gue/aye saya nyai nenek elo/elu kamu empok kakak perempuan langgar masjid abang kakak laki-laki atu satu encing adik ayah/ibu cawan gelas tauke majikan/penguasa tisi sendok centong sendok nasi kagak tidak centeng penjaga kayak seperti syahi teh bagen biarkan pangkeng kamar tidur congor mulut gulem mendung gringsangan tidak mau diam bupet laci babe ayah kempek tas enyak ibu ponten nilai encang kakak ayah/ibu iye iya engkong kakek danta jelas bego dungu
C. Pengaruh Akulturasi Budaya pada Bahasa Betawi
Dialek Betawi banyak mendapat pengaruh baik dari budaya
dalam negeri maupun luar negeri. Pemberi pengaruh yang cukup
35
besar adalah budaya Jawa dan Sunda serta budaya Eropa, Arab, Cina,
dan Melayu. Berikut contoh bahasa Betawi dalam percakapan:
Pengaruh Jawa; ora berarti tidak baik merupakan bahasa Betawi
yang berasal dari bahasa Jawa.
Pengaruh Sunda; dilebok merupakan serapan bahasa sunda
yang berarti makan. Akulturasi ini disebabkan oleh letak
geografis yang bersebelahan.
Pengaruh Eropa; preman merupakan serapan dari bahasa
Belanda yang berasal dari kata vrijman. Dalam bahasa Betawi,
preman berarti orang yang penghasilannya dengan cara
memeras orang lain. Sedangkan dalam bahasa Belanda, vrijman
berarti orang yang bebas.
Pengaruh Arab; ente merupakan serapan dari anta dalam
bahasa Arab yang berarti kamu. Persebaran bahasa Arab di
Jakarta sendiri merupakan salah satu akibat dari perdagangan
dan perkawinan antar etnis.
Pengaruh Cina; goceng biasa digunakan untuk menyebut angka
lima ribu. Cina banyak memberi pengaruh karena bahasa
pasarnya banyak digunakan sebagai bahasa sehari-hari.
Pengaruh Melayu; ciri yang paling khas dari dialek betawi ialah
peralihan bunyi /a/ terbuka di akhir kata menjadi /e/.
D. Pembagian Wilayah Betawi
Tidak hanya di Jakarta, dialek Betawi juga meluas di wilayah
sekitarnya seperti Depok, Tangerang, dan Bekasi. Meski belum ada
kepastian batasannya, secara garis besar wilayah Betawi dapat dibagi
menjadi dua kawasan dialek, yakni Betawi Tengah/Betawi Kota dan
Betawi Pinggir/Betawi Ora.
Betawi tengah melingkupi daerah perkampungan Betawi di
sekitar Jakarta Kota, Sawah Besar, Tugu, Cilincing, Kemayoran, Senen,
Kramat, hingga batas paling selatan di Meester (Jatinegara).
Sedangkan Betawi pinggir melingkupi daerah Jatinegara ke Selatan,
Jagakarsa, Depok, Rawabelong, Ciputat, hingga ke pinggir Jawa barat.
Sebagaimana namanya, Betawi pinggir dominan dipengaruhi oleh
36
bahasa tetangganya seperti Sunda dan Jawa. Akan tetapi juga ada
unsur asingnya.
Beberapa literatur menyebutkan penyebab dari pembagian 2
wilayah Betawi ini salah satunya yaitu pendidikan. Diketahui tengah
sejak abad ke-19 telah tersedia sarana prasarana pendidikan. Di mana
saat itu Belanda sedang melancarkan politik etis. Sedangkan wilayah
Betawi pinggir pada zaman itu merupakan kekuasaan tuan tanah. Sifat
dari tuan tanah ini tidak jauh berbeda dari pemerintah kolonial.
Mereka tidak memedulikan kehidupan warga sekitar. Yang terpenting
bagi mereka adalah hasil bumi yang dapat dihasilkan oleh tanah-tanah
mereka.
Bila dilihat dari segi kesenian Betawi tengah banyak mendapat
pengaruh dari Timur Tengah ditandai dengan masuknya banyak
pembelajaran agama Islam. Sehingga kita kenal dengan rebana,
gambus, dan, kasidahan. Lain hal dengan Betawi pinggir, kesenian
yang berkembang ialah topeng, wayang, dan tanjidor.
E. Perbedaan Dialek
Pembagian geografis masyarakat Betawi menjadi Betawi Tengah
dan Betawi Pinggir juga mencakup perbedaan dialek di antara
keduanya.
Ciri khas yang bersifat tata ucap bahasa Betawi adalah ciri
bahasa Betawi dialek Tengahan. Pertama, pengucapan vokal /a/
terbuka pada akhir kata menjadi /e/ menjadi ciri khas Betawi Tengah
seperti /saye/ (saya), /ape/ (apa). Kedua, pengucapan huruf –ah pada
akhir kata menjadi /e/ seperti /dare/ (darah), /suse/ (susah), /bəle/
belah. Ketiga, pengucapan konsonan /b/, /d/, dan /g/ di akhir kata
pada dialek Tengahan, ketiga konsonan tersebut menjadi fonem tidak
bersuara dari masing-masing konsonannya, misalnya /bədu?/
(bedug), /mulut/ (maulud). Keempat adalah ciri kosakata pada dialek
Tengahan, tidak terdapat kata-kata serapan bahasa daerah seperti ora
(tidak), maka Betawi Tengah menyebut Betawi Pinggir dengan
sebutan Betawi Ora karena menyebut tidak dengan ora.
37
Wilayah pinggiran itu memang terdapat beberapa kosakata yang
tidak digunakan dalam dialek Betawi Tengah seperti kata-kata bocah,
lanang, kulon. Namun ini tidak berarti Betawi Tengah tidak
mengandung serapan kata dari bahasa Jawa, mungkin hanya jarang
atau tidak dipakai.
F. Kesimpulan
Secara umum dapat dipahami bahwa bahasa Betawi yang kita
kenal merupakan bahasa Melayu dialek Betawi. Dalam hal pengaruh,
bahasa Betawi mendapat serapan dari berbagai bahasa seperti bahasa
Sunda, Jawa, Arab, Melayu, Cina, dan Eropa.
Dalam lingkup geografis, dialek Betawi terbagi menjadi Betawi
Tengah dan Betawi Pinggir. Betawi Tengah melingkupi daerah
perkampungan di Jakarta Kota, Sawah Besar, Tugu, Cilincing,
Kemayoran, Senen, Kramat, hingga Jatinegara. Sedangkan wilayah
Betawi Pinggir ialah dari Jatinegara bagian Selatan sampai ke pinggir
Jawa Barat seperti Bogor, dan Depok.
Perbedaan yang mencolok antara Betawi Tengah ialah
pengucapan vokal akhir /a/ menjadi /e/, pengucapan –ah menjadi
/e/, dan tidak terpakainya beberapa kosa kata dari wilayah Sunda dan
Jawa.
38
UNGKAPAN DAN PERIBAHASA DALAM LENONG
SKETSA KOMEDI BETAWI 'DUIT MUTER'
A. Latar Belakang
Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata ungkapan berarti
membuka sementara ungkapan adalah apa yang diungkapkan,
kelompok kata atau gabungan kata yang menyatakan makna khusus
yang merujuk pada objek. Ungkapan juga bisa diartikan sebagai istilah
dalam retorika untuk mencari bentuk satuan bahasa yang digunakan
untuk mengacu pada konsep secara tepat. Sementara pengertian
bahasa Betawi menurut Chaer (2009: 14) merupakan salah satu dialek
regional bahasa Melayu yang digunakan oleh penduduk di wilayah
Jakarta dan sekitarnya. Jadi ungkapan bahasa Betawi merupakan
padanan kata yang diutarakan secara terbuka menggunakan bahasa
Betawi.
Ada anggapan umum dalam masyarakat Betawi bahwa ciri
utama lafal berbahasa Betawi adalah bunyi /a/ dan bunyi /ah/ pada
akhir kata dilafalkan menjadi /e/, seperti kata ‘apa’ menjadi ‘ape’,
‘rumah’ menjadi ‘rume’. Namun anggapan ini tidaklah 100% benar
sebab terdapat perbedaan lafal antara areal satu dengan areal yang
lain maka dari itu karya tulis ini akan menjelaskan tentang ungkapan
dan peribahasa dalam bahasa Betawi, serta memberikan contoh
ungkapan dalam Lenong: Sketsa Komedi Betawi. Pada pembahasan ini
sebaiknya kita lebih memahami terlebih dahulu penggunaan konteks
pengucapan ungkapan bahasa Betawi dan penggunaan konteks
pengucapan peribahasa Betawi.
B. Bahasa Betawi
Bahasa betawi atau Melayu Dialek Jakarta adalah bahasa yang
merupakan akan bahasa dari Melayu. Orang yang menggunakan
bahasa ini bisa disebut “orang Betawi”.
39
Menurut Chaer (2009: 11), bahasa Betawi merupakan salah satu
dialek regional dari bahasa Melayu yang digunakan oleh penduduk di
wilayah Jakarta dan sekitarnya. Karena merupakan dialek regional
dari bahasa Melayu, makan banyak persamaan yang ditemukan.
Sedangkan perbedaannya dilihat dari segi lafal dan jumlah kosa kata.
C. Ungkapan
Menurut Chaer (2009: 14), ungkapan adalah kata, gabungan
kata, atau kalimat yang digunakan oleh pembicara atau penulis untuk
menyatakan suatu hal, maksud, konsep, kejadian, atau keadaan secara
tidak langsung. Maksudnya kata, gabungan kata, atau kalimat itu tidak
digunakan menurut makna aslinya atau makna leksikal, makna
gramatikal, tetapi menurut makna lain yang sedikit banyak masih
mempunyai hubungan atau asosiasi dengan makna aslinya tersebut.
Hubungan atau asosiasi antara makna asli dengan makna lain yang
diwadahi oleh ungkapan itu dapat berupa kiasan, perbandingan,
ataupun persamaan.
Ungkapan bersifat terbuka. Berarti setiap waktu ungkapan itu
dapat bertambah karena orang pandai berbicara maupun menulis dan
memiliki kemampuan untuk menciptakan ungkapan-ungkapan baru.
Namun ada juga kemungkinan terdapat ungkapan-ungkapan yang
membosankan, jarang dipakai, dan akhirnya hilang. Contoh ungkapan
antara lain:
1. Meres keringet (memeras keringat) = bekerja keras
Di sini terdapat hubungan kesamaan peristiwa orang yang
bekerja keras biasanya akan mengeluarkan banyak keringat
sehingga seolah-olah keringatnya tersebut diperas.
2. Buaye darat (buaya darat) = penjahat, maling, penipu
Di sini terdapat persamaan sifat antara orang jahat dengan
buaya, yaitu mengenai kerakusannya sehingga tidak mengenal
lagi barang atau makanan yang baik dan buruk.
3. Ude bau tane (sudah bau tanah) = sudah tua
Ungkapan ini biasanya diaktakan untuk menyebut orang yang
sudah tua, yang hampir meninggal. Orang yang meninggal
40
lazimnya dikubur di dalam tanah. Kalau sudah dikubur yakni
akan berbau tanah. Jadi ada hubungan asosiasi antara bau tanah
dengan orang yang sudah tua.
D. Peribahasa
Peribahasa atau peribase kate (dalam bahasa Betawi) adalah
kelompok kata atau kalimat yang tetap susunannya, biasanya
mengiaskan maksud tertentu. Menurut Chaer (2009: 16) peribahasa
merupakan ungkapan yang biasanya dalam bentuk kalimat. Makna
yang terkandung bisa berupa perumpamaan, persamaan,
perbandingan dengan makna harfiahnya. Contoh peribahasa sebagai
berikut:
1. Dapet duren jatoan (mendapat durian runtuh).
Artinya, seseorang akan mendapat hadiah, pemberian, atau
keuntungan yang sangat besar. Buah duren jatoan biasanya enak
dan masaknya sempurna, berbeda dengan duren sarogan (buah
durian yang jatuh karena batang pohonnya digoyang-goyang)
yang rasanya belum enak dan buahnya belum masak.
2. Kayak anjing dan kucing = dua orang yang selalu ribut.
Pada kenyataan, sifat anjing dan kucing tidak pernah terlihat
akur satu sama lain.
E. Lenong Betawi
Lenong adalah kesenian teater tradisional atau sandiwara
rakyat Betawi yang dibawakan dalam dialek Betawi, berasal dari
wilayah Jakarta. Kesenian tradisional ini diiringi musik gambang
kromong dengan beberapa instrumen seperti gambang, kromong,
gong, kendang, kempor, suling, dan kecrekan. Ada juga instrumen dari
Tionghoa seperti tehyan, kongahyang, dan sukong. Lakon atau
skenario lenong umumnya mengandung pesan moral, misalnya harus
menolong yang lemah atau membenci kerakusan dan perbuatan
tercela. Bahasa yang digunakan tentu saja bahasa Melayu dialek
Betawi.
41
Lenong berkembang sejak akhir abad ke-19. Kesenian teatrikal
tersebut mungkin merupakan adaptasi oleh masyarakat Betawi atas
kesenian serupa seperti “Komedi Bangsawan” dan “Teater Stambul”
yang sudah ada saat itu. Firman Muntaco yang merupakan seniman
Betawi, juga menyebutkan bahwa lenong berkembang dari proses
teaterisasi musik gambang kromong dan sebagai tontonan sudah
dikenal sejak tahun 1920-an. Lakon-lakon lenong berkembang dari
lawakan-lawakan tanpa plot cerita yang dirangkai hingga menjadi
pertunjukan semalam suntuk dengan lakon panjang dan utuh.
Pada mulanya kesenian ini dipertunjukkan dengan mengamen
dari kampung ke kampung. Pertunjukan diadakan di udara terbuka
tanpa panggung. Ketika pertunjukan berlangsung, salah seorang aktor
atau aktris mengitari penonton sambil meminta sumbangan sukarela.
Selanjutnya, lenong mulai dipertunjukkan atas permintaan pelanggan
dalam acara-acara di panggung hajatan seperti resepsi pernikahan.
Baru di awal kemerdekaan, teater rakyat ini murni menjadi
pertunjukan panggung.
Setelah sempat mengalami masa sulit, pada 1970-an kesenian
lenong yang dimodifikasi mulai dipertunjukkan secara rutin di
panggung Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Selain menggunakan unsur
teater modern dalam plot dan tata panggungnya, lenong yang
direvitalisasi tersebut menjadi berdurasi dua atau tiga jam saja dan
tidak lagi semalam suntuk. Selanjutnya, lenong juga menjadi populer
lewat pertunjukan melalui televisi, yaitu yang ditayangkan oleh
Televisi Republik Indonesia (TVRI) mulai tahun 1970-an. Beberapa
seniman lenong menjadi terkenal sejak itu, misalnya Bokir, Nasir, Siti,
dan Anen.
Terdapat dua jenis lenong yaitu leong denes dan lenong preman.
Pada perkembangannya, lenong preman lebih populer dibanding
lenong denes. Dalam lenong denes (dari kata denes dalam dialek Betawi
yang berarti dinas atau resmi), aktor dan aktris umumnya
mengenakan busana formal dan kisahnya bersetting kerajaan atau
lingkungan kaum bangsawan. Sedangkan dalam lenong preman,
busana yang dikenakan tidak ditentukan oleh sutradara dan umumnya
42
berkisah tentang kehidupan sehari-hari. Alur yang dilakonkan dalam
lenong preman misalnya adalah kisah rakyat yang ditindas oleh tuan
tanah dengan pemungutan pajak dan munculnya tokoh pendekar taat
beribadah yang membela rakyat dan melawan si tuan tanah jahat.
Sementara itu, contoh cerita lenong denes ialah Kisah-Kisah 1001
Malam.
Analisis Ungkapan Bahasa Betawi dalam Lenong
Transkrip Dialog Lenong Sketsa Komedi Betawi “Duit Muter”
Bapak 1 : Masya Allah! Rumah udah kayak kapal pecah. Ni
punya anak perawan ke mana lagi nih? Masa
bapaknya nyang mesti ngebersiin ni rumah.
Astaghfirullahalazhim. Gua kagak demen banget nih
ngeliat ni rumah.
Laki : Nyang mane rumenye?
Bini : Ini, bang. Tu bapaknya tu bang yang lagi nyapu tu
bang.
Laki : Ini rumenye?
Bini : Iyee.. sakit bang.
Laki : Samlekom!
Bapak 1 : Kumsalam!
Laki : Bang!
Bapak 1 : Iya.
Laki : Mana anak abang?
Bapak 1 : Siape?
Laki : Anak abang mane?
Bapak 1 : Ada di dalem.
Laki : Eee.. anak abang ni udah nakol pala bini saye ni bang
ni ampe bonyok begini.
Bapak 1 : Ah? Nyang bener? Anak saya kan anak perawan,
nihlok amat dia nakol.
Laki : Yaa. Kagak percaye. Bener kan anaknya dia kan?
Bini : Iye, bang. Anaknya sirik ame aye, bang.
Laki : Pokoknye begini, bang. Aye kagak mau tau. Ni ari
43
abang mesti ngasi perobatan buat bini aye ni palanye
udah bonyok begini nih.
Bapak 1 : Eh ntar dulu, perasaan saye ni bini abang ni emang
palanye rada item.
Bini : Tuh, bang. Aye dikatain, bang.
Laki : Eeeh! Ade-ade aje ni gue bacok bener-bener. Mau
diganti rugi apa kagak?
Bini : Marah dong, bang!
Laki : Pokoknye begini aja, bang, saya kaga mau tau. Ni ari
abang mesti ngasih perobatan buat bini saya.
Bapak 1 : Eeee... ntar dulu. Saya panggil dulu anak saya. Bener
apa nggak dia yang nyambit?
Laki : Aaahhhh! Ga bisa kelamaan! Abang mau saya bacok
emang?! Cepetan! Pooknya langsung aje. Nih dari
semalem nih bang nih die kagak berenti-berenti
nangis. Suaranye ampe serek tuh. Saya mau obatin
langsung sekarang. Mau dikasih kaga?!
Bapak 1 : Yailah, bang.
Laki : Cepetan, bang! Saa bacok bener-bener nih! Udah.
Cepetan!
Bapak 1 : Duit saya semengga-mengga ni. Buat beli beras
rencana nih.
Laki : Lah seraatuus?! Mana cukup?!
Bapak 1 : Yaaaa... cukup ga cukup, obatin. Cuma benyut segitu
doang.
Bini : Enak aje!
Bapak 1 : Ga mao?!
Laki : Gimana nih?
Bapak 1 : Ga mao? Ya udah kalo ga mao.
Bapak 2 : Mana orangnya, man?
Anak 2 : Noh, beh!
Bapak 2 : Berani-beraninya anak gua ditakol-takol!
Anak 2 : Noh! Bininya Oji, noh!
Bapak 2 : Mane orangnye?!
44
Anak 2 : Di sono kali. Jalan aje ke sono, beh.
Laki : Yeee.. sini bang. Mau dikasih kaga si romannye?
Bini : Makanye bilangin anaknye jan berani ame orang tue!
Laki : Yeee. Pokoknya lu udah dikasih, diem lu jan ribut!
Bapak 2 : Samlekom!
Bapak 1 : Kumsalam! Nih apaan lagi nih!
Bapak 2 : Pokoknye aye kagak mau tau!
Anak 2 : Itu, beh!
Bapak 2 : Ah? Inih?
Niat nih anak saye dari ganteng ampe jelek begini.
Pokoknye ga mau tau. Ganti tuh mukenye ampe pada
bonyok!
Laki : Daaaahh... emang anak lu mukanya bonyok. Lu ngapa
jadi nyalahin gue urusannye?!
Bapak 1 : Gue liat!
Laki : Lah emang ngapa sih anak lu?
Bapak 2 : Ngomong dong luh!
Anak 2 : Tuuuuuu.... ama bini abang tuh ditimpuk.
Bapak 2 : Waaaaahhhhhh... pokoknya ga mau tau, bang! Abang
mesti ganti. Ampe ngumpet begitu bini lo.
Laki : Eehh... jan sembarangan ngomong, lu. Nyalah-nyalahin
bini gue nakol pale.
Anak 2 : Lah emang bener, bang!
Laki : Eh! Sini lu Dun. Noh bener anak orang lu takol?
Bini : Iye, bang.
Laki : Ngapa lu nakol anak orang?
Bini : Kaga sengaje, bang.
Laki : Yaaa.. kagak sengaje sampe bonyok begitu.
Bini : Emang die ude bonyok mukenye.
Bapak 2 : Daaah! Jangan banyak bacot dah! Ganti urusannye, gue
mau berobat inih!
Laki : Begimane si, dun! Lu bener anak orang lu timpuk?
Bini : Kagak sengaje aye, bang.
Laki : Aaahhhh.... lu bilang kagak sengaje pala orang ampe
45
bonyok begitu.
Bapak 2 : Ude cepetan dah jangan banyak bacot dah!
Laki : Ude ntar dulu dah bang. Urusin bini saye dulu nih
palanya juga bonyok mau saya obatin dulu.
Bapak 2 : Ntar gua bacok pala lu nih! Apa-apaan?!
Laki : Yaudah ntar dulu dah ntar abis urusan saya baru
urusan abang deh.
Bapak 2 : Kagak bisa pokoknye! Gak bisa! Mesti eni ari diganti!
Laki : Gimane urusannye sih lu, dun! Dah sini dah duitnye!
Bini : Lah abang ganti. Die minta ganti ama abang.
Laki : Eeee... gue duit dari mane. Ude sini bawa sini!
Bini : Ya elah.
Laki : Ude lu sini daripade gua dibacok orang luh.
Bini : Biarin aje, orang yang dibacok abang.
Laki : Enak aje luh! Ude tuh! Elu gare-garenye tuh!
Anak 1 : Babeeee.... muka aye sakit beh.
Bapak 1 : Ya Allah neng, lu cakep-cakep ngapa jadi begini, neng?
Siapa yang galakin?!
Anak 1 : Itu tu, beh! Die goda-godain aye.
Bapak 1 : Naaahhh... ini biang keladinye ye! Eeeeh .. ini gue mesti
minta ganti rugi. Gue ga terima anak gue yang boto
begini ampe bengep begini!
Bapak 2 : Eh lu apain anak orang?
Anak 2 : Godain, beh. Dia kagak mau.
Bapak 1 : Eetttt... lu kagak pantes godain anak gue, tau ga lo!?
Laki : Nah loh, tau kaga lo?
Bapak 2 : Ayo pulang!
Bapak 1 : Eeeeeh... kaga bisa! Lu berobatin anak gue!
Laki : Gantiiiii... gue tadii ganti barusan. Lu ganti! Kan sama-
sama bonyok. Ude lu kasih noh!
Bapak 1 : Ooohhhh... ini duit buat berobat neng. Aaaah tapi ini
duit, duit gue juga. Eeeeh.. bikin kesel gue nih. Ayo,
neng!
Bapak 2 : Mat!
46
Anak 2 : Iye, beh!
Bapak 2 : Begimane urusannye nih? Aaahh.. lu bikin malu babe
aja luh. Ayo pulang!
Anak 2 : Pulang aje deh beh.
Bapak 2 : Eeehhh. Dapet kagak, tuh duit!
Bini : Bang, ga jadi berobat dong aye?
Laki : Yaa... salah eluh! Ngapa anak orang lu timpuk?!
Bini : Yeee.. itu masa abang takut sama die begitu aje?
Laki : Bukan masalah takut. Lu salah! Kalo die lapor polisi?
Enak aje luh! Ude ntar gampang berobat dah. Aaahhh..
gara-gara elu!
F. Analisis Ungkapan dalam Lenong: Sastra Komedi Betawi
“Duit Muter”
Kalimat Ungkapan Arti Masya Allah... Rumah udah kayak kapal pecah
kapal pecah berantakan
Anak abang ni udah nakol pala bini saye nih bang nih ampe bonyok begini
nakol memukul bonyok memar
Anak saya kan perawan, nihlok amat dia nakol
nihlok tidak mungkin
Bener apa enggak dia yang nyambit
nyambit menghajar
Duit saya semengga-mengga nih semengga-mengga sedikit-sekali Beraninya anak gua ditakol-takol ditakol-takol dipukul Ini biang keladinye biang keladi pelaku
G. Ungkapan dalam Bahasa Betawi dengan Konteksnya
Selain ungkapan yang terdapat dalam transkripsi dialog lenong
di atas, terdapat pula beberapa contoh ungkapan dalam bahasa
Betawi, di antaranya:
Ungkapan Arti Konteks kapal pecah berantakan melihat keadaan yang
berantakan nakol memukul membahas mengenai per-
47
Ungkapan Arti Konteks kelahian
bonyok memar melihat bekas pukulan setelah berkelahi
nihlok tidak mungkin menyangkal sesuatu nyambit menghajar membahas mengenai per-
kelahian semengga-mengga sedikit-sekali mengeluh karena mem-
punyai sesuatu yang sedikit ditakol-takol dipukul membahas mengenai per-
kelahian biang keladi pelaku menemukan dalang dari
suatu permasalahan aer ame minak dua hal yang tidak
dapat disatukan melihat dua orang yang selalu berselisih
aer besar tinja; tai; kotoran manusia
saat ingin ke kloset
aer di daon tales selalu berubah pen-dirian
sedang menasihati orang yang labil/berubah-ubah keputusannya
amplop tebel uang sogok dalam jumlah besar
menerima uang banyak
aer kecil kencing; urin saat ingin ke kloset aer selalu nyari jalan nyang turun
kejadian/hal yang biasa saat menasihati
anak baru kemaren masih muda; belum berpengalaman
meremehkan orang yang lebih muda karena masih minim pengalaman
aer mate buaye pura-pura sedih/berduka; menipu
melihat orang yang pura-pura bersedih
aer mate dara sangat sedih berduka terhadap orang yang kesedihannya men-dalam
aer muke rupa muka/wajah; sangat sedih
mendeskripsikan ekspresi orang lain
ahli kubur orang-orang yang sudah dikuburkan
menyebut orang yang telah dikubur di makam
ahli permili anggota kerabat yang banyak
dalam acara tertentu yang mendatangkan banyak anggota keluarga
ampir asar sudah tua menasihati orang yang sudah tua agar cepat taubat
ampir magrib sudah sangat tua menasihati orang yang
48
Ungkapan Arti Konteks sudah tua agar cepat taubat
amplop kosong gaji yang habis karena bayar hutang
melihat orang bersedih gajinya habis
anak bau kencur masih kecil menganggap anak muda/ anak-anak nakal karena belum mengerti apapun
banyak lagu bertingkah laku men-jengkelkan
melihat orang yang tingkah lakunya berlebihan
banyak mulut suka membantah; cerewet; banyak ber-alasan
merasa jengkel ketika berhadapan dengan omong-an orang yang tiada henti
banyak tingke bertingkah laku men-jengkelkan
melihat orang yang tingkah lakunya berlebihan
barang antik wanita cantik yang sombong
melihat wanita cantik tetapi angkuh perilakunya
H. Peribahasa Bahasa Betawi dan Konteksnya
Berikut ini adalah contoh-contoh peribahasa dalam bahasa
Betawi dan konteks penggunaannya:
Peribahasa Makna Konteks aer selalu nyari jalan nyang turun
Kejadian atau hal yang biasa.
Saat ada kejadian yang sudah biasa terjadi dan merupakan kodrat alam.
aer laut siape nyang asinin
Siapa yang bisa membuat air laut menjadi asin (memang sudah asin) adalah orang sombong.
Saat mendengar orang yang sedang menyom-bongkan dirinya.
anak ame babe sama aje
Sifat yang tidak berubah setelah diturunkan ke anaknya.
Melihat tingkah laku seorang anak sama persis dengan orang tuanya.
anak arab pulang ke arab, anak cina pulang ke cina
Janji harus kembali (harus ditepati).
Saat ada orang berjanji agar ia menepati janjinya
anak ayam kagak ninggalin biangnye
Anak tidak akan meninggalkan (meng-abaikan) keluarganya begitu saja.
Saat ingin merantau, saat mempertanyakan kepe-dulian anak terhadap keluarganya.
49
Peribahasa Makna Konteks banyak makan asem garem
Sudah banyak pengala-man yang dilalui dalam kehidupan.
Saat ada orang meragu-kan kemampuan orang yang sudah ahli atau sukses di bidang tertentu.
banyak-banyak jadi minyak
Sesuatu yang ber-lebihan tidaklah baik.
Menasihati seseorang yang suka rakut, menim-bun, menyimpan sesuatu yang banyak, atau serakah.
dalem laut dapat diduge, dalem ati siape nyang tau
Seseorang tidak dapat melihat isi hati orang lain.
Saat menasihati orang yang selalu berprasangka terhadap niat orang lain.
dari ujung kaki ampe ke ubun-ubun
Secara keseluruhan. Mengamati sesuatu secara keseluruhan.
deket bau wangi, jauh bau bangke
Bila berdekatan selalu akrab, namun ketika jauh selalu bermusuhan.
Melihat seseorang dengan orang lain saling membenci saat tidak berhadapan satu sama lain.
denger geludug di siang bolong
Sangat terkejut. Ketika kaget/terkejut secara tiba-tiba.
die mau nyubit, kite cubit duluan
Dahuluan melakukan sesuatu ke orang lain sebelum ia melakukan sesuatu kepada kita.
Ketika hendak berkelahi, memukul, dsb.
duduk di tiker nyang digelarin
Hidup selalu mudah; menikah tanpa biaya.
Melihat seseorang yang hidupnya selalu terlihat mudah dan tenang dengan usaha yang sedikit.
dunie ga selebar daun kelor
Kesempatan untuk memperoleh sesuatu di dunia masih dapat dicapai.
Menasihati seseorang yang gagal dalam suatu urusan agar mencoba hal lain.
ente baru jadi kadal, ane ude jadi buaye
Kamu belum menjadi apa-apa, saya sudah jadi penjahat besar.
Digunakan ketika bos atau atasan penjahat melihat bawahannya terlalu sombong.
50
I. Kesimpulan
Ungkapan dan peribahasa Betawi rupanya sangat banyak.
Terlihat dari analisis dan temuan di bagian isi dari karya tulis ini
bahwa banyak ungkapan-ungkapan dan peribahasa yang terdengar
unik bagi yang belum pernah mendengarnya. Tentunya peribahasa
dan ungkapan tersebut tidak serta-merta tercipta begitu saja, tetapi
masyarakat Betawi sudah menggunakannya sejak lama. Bahkan
ungkapan dan peribahasa tersebut menjadi ciri khas bagi mereka.
Ungkapan dan peribahasa juga sering kali dimasukkan dalam kesenian
lenong mereka sebagai bukti bahwa identitas masyarakat Betawi
mengenal nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari.
51
KEPUNAHAN BAHASA BETAWI
DI SRENGSENG SAWAH
A. Latar Belakang
Pada hakikatnya, bahasa merupakan alat komunikasi dominan
bagi manusia. Berdasarkan wilayah penggunaannya, bahasa
dibedakan menjadi bahasa asing, bahasa nasional, dan bahasa daerah.
Berdasarkan keadaan penggunaannya, bahasa dibedakan menjadi tiga
yaitu pemertahanan bahasa, pergeseran bahasa, dan kepunahan
bahasa (Sumarsono, 2012: 231).
Hasil Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam artikel
“Menggali Bahasa yang Nyaris Punah” yang terbit di koran Tempo, 18
Maret 2012 menyatakan bahwa Indonesia memiliki 756 bahasa
daerah. Telah tertulis dan ditetapkan dalam UU No.22/1999 mengenai
pemerintahan daerah, kewenangan penanganan bahasa dan sastra
yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Keadaan yang
terjadi saat ini yaitu sekitar 30% bahasa daerah di Indonesia terancam
punah, salah satunya adalah bahasa Betawi, bahasa yang merupakan
hasil dari percampuran bahasa Melayu dengan bahasa lain.
Berdasarkan ulasan di atas maka kita perlu mengetahui
bagaimana kepunahan bahasa betawi di serengseng sawah,
selanjutnya masalah kepunahan ini perlu dianalisis bagaimana
kepunahan bahasa betawi terjadi dan apa upaya yang bisa dilakukan
untuk mempertahankan bahasa betawi di serengseng sawah.
B. Kepunahan Bahasa Betawi
Ilmu untuk mengetahui adanya kepunahan dalam bahasa perlu
mengetahui teori bahasa tentang sosiolinguistik, Bilingualisme dan
Diglosia, Pergeseran Bahasa, Pemertahanan Bahasa, Kepunahan
Bahasa.
52
C. Sosiolinguistik
Sosiolinguistik adalah kajian tentang bahasa yang dikaitkan
dengan kondisi kemasyarakatan. Menurut Chaer (2004: 2),
sosiolinguistik adalah bidang ilmu antar disiplin yang mempelajari
bahasa dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa itu di dalam
masyarakat. Sumarsono (2007: 2) mendefinisikan sosiolinguistik
sebagai linguistik institusional yang berkaitan dengan pertautan
bahasa dengan orang-orang yang memakai bahasa itu. Sedangkan
Rafiek (2005: 1) mengatakan bahwa sosiolinguistik sebagai studi
bahasa dalam pelaksanaannya itu bermaksud/bertujuan untuk
mempelajari bagaimana konvensi-konvensi tentang relasi penggunaan
bahasa untuk aspek-aspek lain tentang perilaku sosial.
D. Bilingualisme dan Diglosia
Masyarakat bahasa adalah masyarakat yang menggunakan satu
bahasa yang disepakati sebagai alat komunikasinya. Dilihat dari
bahasa yang digunakan dalam suatu masyarakat bahasa, masyarakat
yang menggunakan satu bahasa dan masyarakat yang menggunakan
dua bahasa atau lebih. Masyarakat dengan satu bahasa dinamakan
monolingual, dua bahasa yaitu bilingual, sedangkan yang
menggunakan lebih dari dua bahasa disebut multilingual.
Di era modern, jarang ditemukannya masyarakat monolingual
kecuali di daerah-daerah terpencil, biasanya terkait dengan faktor
tradisi, genetik, dan geografis. Di Indonesia, banyak terdapat
masyarakat bilingual karena sebagian besar menggunakan bahasa
daerahnya (Sunda, Jawa, Batak, Betawi, dll.) dan bahasa nasional
Indonesia.
Diglosia adalah suatu situasi bahasa di mana terdapat
pembagian fungsional atas variasi-variasi bahasa atau bahasa-bahasa
di masyarakat. Diglosia ditandai dengan penggunaan dua unsur
bahasa atau lebih dalam masyarakat, tetapi masing-masing bahasa
mempunyai fungsi atau peranan yang berbeda dalam konteks sosial.
Misalkan formal dan informal, kedua ragam bahasa ini memiliki fungsi
masing-masing dalam masyarakat di Indonesia. Ragam formal
53
digunakan ketika acara-acara resmi atau dalam suatu lembaga,
sedangkan ragam tidak formal dapat digunakan untuk percakapan
sehari-hari. Penggunaan bahasa asing dan bahasa daerah juga dapat
memasuki wilayah diglosia jika fungsinya berbeda dengan bahasa
utama di masyarakat tersebut.
E. Pergeseran Bahasa
Pergeseran bahasa yaitu menempatkan sebuah bahasa menjadi
lebih penting di antara bahasa-bahasa yang dikuasai. Banyak faktor
yang dapat dijadikan alasan masyarakat bahasa melakukan
pergeseran bahasa, yaitu faktor perpindahan penduduk, ekonomi,
pendidikan, dan lain-lain.
F. Pemertahanan Bahasa
Konsep pemertahanan bahasa lebih berkaitan dengan prestise
suatu bahasa di masyarakat penuturnya. Suatu masyarakat bahasa
disebut mempertahankan bahasa apabila tetap menggunakan B1
(bahasa awal/bahasa pertama yang dikuasai) ketimbang B2 dalam
keadaan bilingual atau multilingual. Biasanya pemertahanan bahasa
disebabkan oleh teknologi yang semakin berkembang sehingga orang
tidak perlu lagi mempelajari bahasa asing untuk mengakses informasi
karena sudah tersedia dalam bahasanya; lalu ada prestise atau
kebanggaan suatu masyarakat bahasa terhadap bahasanya yang
menyebabkan posisi bahasa utama mereka menjadi dominan; lalu ada
juga pendidikan bahasa daerah, dan lain-lain.
G. Kepunahan Bahasa
Bahasa memperoleh “jatah hidup” dari masyarakat dan
budayanya. Nasib bahasa terkait dengan penuturnya dan jika
penggunaan bahasa menurun atau mendekati kepunahan, hal itu
hanya dapat terjadi karena keadaan penuturnya telah berubah.
Menurut Kloss (1984), ada tiga tipe utama kepunahan bahas, yaitu:
1. Kepunahan bahasa tanpa pergeseran bahasa (guyub tuturnya
lenyap).
54
2. Kepunahan bahasa karena pergeseran bahasa (guyub tutur
tidak berada dalam wilayah tutur yang kompak atau bahasa
tersebut tidak kuat menghadapi dinamika intrinsik prasarana
budaya modern).
3. Kepunahan bahasa nominal melalui metamorfosis (bahasa turun
derajat menjadi hanya dialek saja karena minimnya
perkembangan dan reproduksi bahasa menggunakan tulisan
atau ejaan dari bahasa lain).
Secara keseluruhan, penyebab paling jelas adalah tidak
cukupnya konsentrasi penutur dan bahasa yang tidak dinamis
menghadapi lingkungan yang kuat secara ekonomi dan teknologi.
Namun secara umum, disebabkan oleh tidak adanya transmisi atau
warisan bahasa dari orang tua kepada anak-anaknya.
H. Analisis Kepunahan Bahasa Betawi di Srengseng Sawah
1. Sikap Bahasa Betawi
Menurut Suwito (1982: 59) sikap positif bahasa dibedakan
menjadi tiga, sebagai berikut:
1) Kebanggaan bahasa dalam penggunaan bahasa Betawi dan
Bahasa Indonesia pada suku Betawi di Srengseng Sawah, Jakarta
Selatan.
Kebanggaan bahasa merupakan sikap yang mendorong
seseorang atau sekelompok orang untuk menjadikan bahasanya
sebagai identitas pribadi atau kelompok. Pada penelitian ini,
sikap kebanggaan terhadap 7 bahasa Betawi masih ditunjukkan
oleh generasi tua, sedangkan generasi muda sudah mulai
mengurangi rasa bangga terhadap bahasa Betawi.
2) Kesetiaan bahasa dalam penggunaan bahasa Betawi dan bahasa
Indonesia pada suku Betawi di Srengseng Sawah, Jakarta
Selatan.
Kesetiaan bahasa adalah sikap yang mendorong suatu
masyarakat tutur untuk mempertahankan kemandirian
bahasanya, meskipun harus mencegah masuknya pengaruh
asing. Generasi tua lebih banyak memakai bahasa Betawi dalam
55
ranah kekeluargaan, ketetanggaan, dan adat terhadap
interlokutor yang lebih tua maupun muda. Kemudian pada
generasi muda sudah mulai mengurangi penggunaan bahasa
Betawi terlihat pada beberapa ranah seperti ranah ketetanggaan
tetapi hanya terhadap interlokutor berusia lebih tua.
3) Kesadaran adanya norma bahasa dalam penggunaan bahasa
Betawi dan Bahasa Indonesia.
Kesadaran adanya norma bahasa adalah sikap dari dalam diri
yang mendorong penggunaan bahasa secara cermat, santun,
korek, dan layak. Sikap kesadaran akan norma terhadap bahasa
Betawi masih ditunjukkan oleh kedua generasi dari suku
Betawi.
2. Nasib Bahasa Betawi
Sejak dahulu nasib bahasa Betawi telah diprediksi oleh
beberapa ahli dari hasil penelitian mengenai bahasa Betawi (Muhadjir,
1999: 107-108).
1. Menurut Ben Anderson (1966) mengenai bahasa Betawi dan
bahasa Indonesia dengan tingkat kebahasaan.
2. Kay Ikranegara dalam disertasinya (1980), berpendapat bahwa
bahasa Indonesia dan bahasa Betawi adalah hubungan antara
dua dialek dari satu bahasa yang sama.
3. Muhadjir (1976) menyatakan bahasa Betawi dalam
perkembangannya akan menjadi ragam bahasa Indonesia
substandar. Nasib 8 bahasa Betawi di masa mendatang
menunjukkan posisi kepunahan nominal atau hanya punah pada
penggunaan.
3. Faktor Penyebab Kepunahan/Kebertahanan Bahasa Betawi
Proses kepunahan bahasa Betawi yang termasuk kepunahan
nominal seperti telah dikelaskan oleh teori Kloss (1984). Kepunahan
nominal adalah kepunahan yang disebabkan oleh dua faktor yaitu
internal dan eksternal (Muhadjir, 1999: 110). Kebertahanan bahasa
Betawi masih ditunjukkan oleh suku Betawi di Srengseng tetapi hanya
keadaan sebagian. Berbeda pendapat dengan Muhadjir, Sumarsono
56
(2012) mengatakan bahwa faktor internal dan eksternal juga terjadi
pada kebertahanan bahasa seperti pada penelitian pemertahanan
bahasa Melayu Loloan.
a) Kepunahan Nominal
1) Faktor Internal
Berkurangnya peredaran kosakata bahasa Betawi.
Berkurangnya jumlah penutur asli.
Kurang pengenalan bahasa Betawi pada generasi
berikutnya.
2) Faktor Eksternal
Pengurangan penggunaan bahasa Betawi pada beberapa
ranah
b) Kebertahanan Sebagian
1) Faktor internal
Adanya sikap konsekuensi dari suku Betawi.
Terdapat sikap positif terhadap bahasa Betawi oleh suku
Betawi.
Terdapat penggunaan bahasa Betawi dalam ranah
kekeluargaan, ketetanggaan, dan adat.
Adanya rasa keingintahuan pada generasi muda.
2) Faktor eksternal
Adanya sikap toleransi terhadap bahasa Betawi.
Masih terdapat media massa yang menggunakan bahasa
Betawi.
4. Upaya untuk Menjaga Eksistensi Bahasa Betawi
a) Suku Betawi
Masih menggunakan bahas Betawi pada beberapa ranah.
Masih memakai kebudayaan Betawi pada acara tertentu.
Masih ada media massa yang menggunakan bahasa Betawi.
b) Pemerintah
Adanya undang-undang tentang bahasa daerah, khususnya
bahasa Betawi.
Penelitian terhadap bahasa Betawi maupun budaya Betawi.
57
5. Upaya untuk Menjaga Eksistensi Bahasa Betawi
a) Suku Betawi
Masih menggunakan bahas Betawi pada beberapa ranah.
Masih memakai kebudayaan Betawi pada acara tertentu.
Masih ada media massa yang menggunakan bahasa Betawi.
b) Pemerintah
Adanya undang-undang tentang bahasa daerah, khususnya
bahasa Betawi.
Penelitian terhadap bahasa Betawi maupun budaya Betawi.
I. Kesimpulan
Diprediksi bahwa bahasa Melayu dialek betawi telah mengalami
kemusnahan di beberapa wilayah di DKI Jakarta. Hal ini disebabkan
hilangnya tanah dan masyarakat yang menjadi pelaku bahasa dan
budaya masyarakatnya. Daerah DKI Jakarta secara keseluruhan,
mengalami pergeseran dan kepunahan suatu bahasa karena tidak
cukupnya konsentrasi penutur dan bahasa yang tidak dinamis
menghadapi lingkungan yang kuat secara ekonomi dan teknologi. Ada
2 hal yang menyebabkan secara umum yaitu faktor internal dan faktor
eksternal. Faktor internal disebabkan oleh adanya sikap konsekuensi
dari suku Betawi, Terdapat sikap positif terhadap bahasa Betawi oleh
suku Betawi. Terdapat penggunaan bahasa Betawi dalam ranah
kekeluargaan, ketetanggaan, dan adat. Adanya rasa keingintahuan
pada generasi muda. Faktor eksternal Adanya sikap toleransi terhadap
bahasa Betawi. Masih terdapat media massa yang menggunakan
bahasa Betawi.
58
KARAKTERISTIK PERKAMPUNGAN BUDAYA
BETAWI
A. Profil Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan
Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan merupakan media
apresiasi para wisatawan, peneliti, dan masyarakatnya terhadap
potensi yang ada. Perkampungan Budaya Betawi (PBB) harus menjadi
tempat rekreasi sekaligus sebagai pusat informasi untuk menambah
pengetahuan tentang karakteristik kebetawian. Keberadaan Pusat
Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan yang terletak di
Kampung Srengseng Sawa, Kecamatan Jaga Karsa Jakarta Selatan.
Perkampungan Setu Babakan seluas 289 hektar didirikan
dengan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 9 tahun 2000.
Gapura masuk dengan ukiran kayu yang unik sebagai pintu utama,
Ketika memasuki area pertunjukan terdapat bangunan rumah kayu
berarsitektur kebetawian. Selain bangunan rumah dengan hiasan
pagar kayu berukir, juga terdapat panggung besar di areal tengah.
Panggung dikitari oleh tempat duduk penonton yang berbentuk U
bersusun dan di belakang tempat penonton dibatasi oleh bangunan
arsitektur klasik yang tinggi, di situlah sebagai bangunan perkantoran
UPK yang dipimpin oleh seorang Kepala, Wakil Kepala, dan staf. Acara
pertunjukan dijadwalkan oleh UPK yang bekerja sama dengan Kepala
Dinas Pariwisata DKI Jakarta, Bamus DKI Jakarta, LKB. Penjadwalan
pertunjukan disesuaikan dengan hari libur atau hari penting lainnya,
seperti pada hari Sabtu dan Minggu diadakan pementasan bagi
sanggar-sanggar seni dari mana pun di wilayah DKI, pementasan itu
berupa pertunjukan musik gambang kromong, gambang rancag,
lenong, sahibul hikayat, topeng, dan beberapa prosesi upacara
pernikahan, sunatan, akikah, khatam quran dan nujuh bulan ala
Betawi.
59
Peran dan fungsi perkampungan Setu Babakan dalam upaya
pelestarian dan pengembangan kesenian Betawi menunjukkan, bahwa
masih jauh api dari panggangannya, peran dan fungsi Setu Babakan
belum maksimal. Setu Babakan diharapkan dapat dijadikan pusat
perkampungan budaya Betawi sebagai trend setter sehingga
wisatawan dan peneliti atau orang yang datang ke Setu Babakan dapat
mengapresiasi pertunjukan yang dibutuhkan. Perlu ada upaya untuk
membuat model karakteristik pertunjukan di PBB Setu Babakan.
Adanya atraksi upacara maupun prosesi budaya, seperti pada
acara Lebaran Betawi, yang beberapa tahun belakangan ini sudah
rutin dilakukan, termasuk peringatan HUT DKI Jakarta, dan acara
kemeriahan yang dijadwalkan oleh UPK Setu Babakan dijadikan
sebagai identitas keberadaan Setu Babakan sebagai cagar budaya
Betawi. Adanya upaya bertahan dari gempuran modernisasi dan
globalisasi. Begitulah, Setu Babakan telah dilihat sebagai wilayah yang
masih memelihara keaslian budaya Betawi, ketika tempat-tempat lain
di Jakarta hal tersebut sudah tidak ada lagi. Kampung-kampung orang
Betawi telah digusur demi pembangunan metropolitan Jakarta.
Kantong-kantong budaya Betawi ikut lenyap karenanya. Setu Babakan
seperti membayar kembali kerinduan orang akan kawasan konservasi
budaya Betawi yang sebelumnya sudah jarang ditemui (Cicih dkk.,
2013).
Tentu kehadiran PBB dibutuhkan adanya sikap kreatif dari
seniman-seniman Betawi untuk melakukan rekonstruksi terhadap
kesenian budaya Betawi yang kurang mendapat sambutan. Kondisi
memprihatinkan ini membawa kekhawatiran dalam pengembangan
seni budaya Betawi terutama peran dan fungsi perkampungan Setu
Babakan dalam upaya pelestarian dan pengembangan kesenian
Betawi harus disikapi dengan arif. Mulai dari demografi Setu Babakan
yang sedari awal telah terjadi dan mempertanyakan pilihan pada
wilayah Setu Babakan. Keberadaan Setu Babakan diharapkan tidak
berlaku, seperti Taman Mini Indonesia yang kini telah berubah fungsi
hanya sebagai tempat rekreasi. Perkampungan Setu Babakan harus
menjual hal yang berbeda bagi para pengunjungnya, setidaknya
60
kedatangan pengunjung Setu Babakan dapat memperoleh berbagai
hal, sehingga nantinya Setu Babakan dapat menjadi Trend Setter
sebagai pusat kajian atau tempat untuk mengapresiasi pertunjukan
seni budaya Betawi yang berkarakter.
B. Implementasi Setu Babakan sebagai Perkampungan Betawi
Pengimplementasian daerah Setu Babakan sebagai
Perkampungan Budaya Betawi (PBB) merupakan aktualisasi cita-cita
dan impian masyarakat Betawi melalui organisasi-organisasi
kebetawian serta usaha dari para tokoh Betawi dan pemerintah
melalui Dinas Pariwisata DKI Jakarta. Pengelolaan Industri Kreatif
Pertunjukan di PBB Setu Babakan
Latar belakang data di atas melahirkan upaya untuk
melanjutkan model karakteristik Perkampungan Budaya Betawi yang
selanjutnya disebut PBB di Setu Babakan, dengan cara meningkatkan
industri kreatif berdasarkan karakter budaya yang telah dikaji dalam
tahun I penelitian, Selanjutnya luaran penelitian tahun I yaitu
rancangan bahan ajar model karakteristik PBB di Setu Babakan
berupa pertunjukan gambang rancag, lenong, topeng, gambang
kromong, dan berbagai tarian dan musik Betawi, termasuk kuliner dan
arsitektur rumah Betawi, Pada tahun II ini selanjutnya dioptimalkan
semua modal karakter tersebut agar dapat memberi manfaat bagi
masyarakat perkampungan budaya PBB khususnya dan umumnya
menjadi model pengembangan melalui industri kreatif di wilayah lain
di seluruh Indonesia. Kemudian dibuatlah model industri kreatif dari
karakter PBB Setu Babakan dan perkampungan budaya di wilayah lain
dalam bentuk bahan ajar yang akan disosialisasikan dengan tujuan
kegiatan ini dapat bermanfaat secara langsung kepada masyarakat
sekitar perkampungan Setu Babakan juga wilayah lain melalui
pengembangan industri kreatif yang mendukung keberlangsungan
ekonomi masyarakat. Adapun hal yang akan dijawab dalam penelitian
ini, yaitu (1) bentuk pengelolaan industri kreatif PBB Setu Babakan
sebagai wujud untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Setu
Babakan dan dapat dijadikan model perkampungan budaya di seluruh
61
Indonesia, (2) bentuk atau pola industri kreatif dioptimalkan dalam
mengelola PBB sebagai bentuk karakteristik budaya, dan (3) model
bahan ajarnya sebagai industri Budaya Betawi Setu Babakan.
Karakteristik perkampungan budaya Betawi meliputi nilai-nilai
yang terkandung dalam hidup masyarakat Betawi. Hal yang termasuk
dalam kehidupan masyarakat Betawi, meliputi, cara hidup berita adat
istiadat, kesenian, kuliner, dan arsitektur. Berikut akan dijelaskan
beberapa karakteristik dalam pertunjukan seni di Perkampungan Setu
Babakan.
C. Pertunjukan Gambang Rancag
Pertunjukan gambang rancag yang merupakan karakter hidup
masyarakat Betawi telah dilestarikan oleh komunitas Putra Jali
dengan berkolaborasi dengan pemain mudah yunior. Kelompok Putra
Jali mewariskan ilmu merancag dengan ara merancag bareng adalah
sebuah bentuk pengelolaan yang membuka pewarisan pada orang lain
di luar keluarga inti yang selama ini tertutup. Tujuan kolaborasi ini
sebagai bentuk penelitian untuk mendapatkan model karakter
perkampungan budaya Betawi berupa bentuk pengelolaan
pertunjukan yang mampu berkolaborasi dengan bintang komunitas
tradisi yang telah memiliki jam terbang, tujuannya saling memberi
pengalaman dan pengetahuan, termasuk penurunan atau pewarisan
pertunjukan yang berkarakter dengan cara bertukar ilmu dalam
pertunjukan antara pemain muda dengan senior.
Pengelolaan pertunjukan gambang rancag adalah salah satu
bentuk sastra lisan Betawi. Saputra (2009, hlm. 8) mengemukakan
bahwa “gambang rancag adalah seni sastra yang memiliki dua kata,
yaitu gambang berarti musik pengiringnya dan rancag adalah cerita
yang dibawakan dalam bentuk pantun berkait dan syair.”
62
Gambar 2. Gambang Rancag
(Dok. Pribadi 23/52018)
Istilah ngerancag menurut Kamus Dialek Jakarta (dalam Chaer,
2009, hlm. 372) berarti (1) menetak-netak, memenggal-menggal,
memotong-motong; (2) penuturan cerita dengan diiringi musik
gambang kromong. Istilah tersebut juga dipaparkan oleh Kunst (1934,
hlm. 308) dalam bukunya yang berjudul Do Toonkunst van Java yang
menyatakan bahwa:
gambang rancag yang hidup di Batavia dan daerah sekitarnya yang memperoleh pengaruh Cina, digunakan untuk mengiringi cerita-cerita yang dinyanyikan (apa yang disebut syair) tentang kejadian mengesankan yang terjadi pada tahun-tahun silam, misalnya cerita Pitung Rampok Betawi, cerita Angkri Digantung di Betawi, cerita Delep Kelebu di Laut, dan biasanya sebagai pembuka diiringi dengan lagu-lagu seperti Jali-Jali, Persi, Surilang, Lenggang Kangkung, Keramet Kerem, dan sebaginya, serta diiringi alat musik yang terdiri dari gambang kayu, kenong, dan gendang.
63
Selain itu, Sopandi dkk. (1999, hlm. 76−77) dalam buku
Gambang Rancag oleh Dinas Kebudayaan DKI Jakarta mengemukakan
bahwa:
gambang rancag berasal dari dua kata, yaitu kata gambang dan rancag. Istilah gambang diartikan sebagai instrumen pokok dalam orkes gambang kromong yang digunakan untuk mengiringi nyanyian sebagai sarana penampilan cerita dalam bentuk pantun berkait. Selanjutnya, kata rancag adalah cerita-cerita rakyat Betawi dalam bentuk pantun atau syair yang dinyanyikan oleh dua orang penyanyi pria, dengan irama dan melodi yang cepat.
Sejarah gambangrancag dimulai sekitar awal abad XVIII,
berawal ketika proses pembauran antara orang pribumi dengan
orang-orang Cina terjadi. Disebutkan oleh Thomas Ataladdjar (dalam
Widodo, 2010, hlm. 10) bahwa:
“pada tahun 1740 pasukan kaum Cina—yang merasa ditekan oleh beberapa pejabat VOC dengan sistem pajak untuk memperkaya diri melakukan pembalasan dengan cara membunuh beberapa pejabat VOC. Selanjutnya pihak VOC juga membalas dengan kembali melakukan pembunuhan massal terhadap orang-orang Cina, yaitu sekitar 1000 orang Cina terbunuh, termasuk 500 tahanan dan pasien rumah sakit. Peristiwa itu terjadi pada 9 Oktober 1740. ”
Akibat peristiwa itu, sebagian besar masyarakat Cina,
khususnya orang-orang yang berada pada kelas bawah, lebih memilih
keluar dari Batavia. Sementara, mereka yang berada di kelas atas tetap
meneruskan kehidupan dengan berdagang di dalam area Batavia.
Orang-orang Cina yang keluar Batavia menyebar dan banyak
melarikan diri ke pinggiran Batavia, seperti daerah Babelan, Tambun,
Bekasi, Lemahabang, Tangerang, Ciampea, Lewiliyang, Jonggol,
Cileungsi, Cibarusa dan beberapa daerah di sekitar Jakarta. Berikut
digambarkan dalam peta wilayah penyebaran masyarakat Cina dan
pribumi dari sumber Mededeelingen No. 5 van het Encyclopaedish
Bereau van de Kononklijke Verceni ging “Koloniaal Instituut”, Do
64
Bevolking va de Regentsscheppen Batavia, Mester Cornelis en
Buitenzorg, (1933, hlm. 8) sebagai berikut.
Gambar 3. Peta wilayah Batavia dan sekitarnya sebagai wilayah
penyebaran orang-orang Cina ke daerah pinggiran kota Batavia
(Sumber: Mededeelingen No. 5 van het Encyclopaedish Bereau van de
Kononklijke Verceni ging “Koloniaal Instituut”, Do Bevolking va de
Regentsscheppen Batavia, Mester Cornelis en Buitenzorg, 1933, hlm. 8)
Data pada Mededeelingen No. 5 van het Encyclopaedish Bereau
van de Kononklijke Verceni ging “Koloniaal Instituut”, Do Bevolking va
de Regentsscheppen Batavia, Mester Cornelis en Buitenzorg
menjelaskan bahwa di wilayah tempat pelarian saat itu banyak orang-
orang Cina yang melakukan perkawinan campur dengan orang-orang
pribumi. Pembauran orang-orang Cina dengan pribumi juga ditandai
dengan masih ditemukannya sampai sekarang beberapa peninggalan
klenteng (tempat ibadah) di wilayah tersebut. Contohnya klenteng tua
65
di Cibinong yaitu Klenteng Tanjung Kuit yang terletak 7 Km dari Mauk.
Klenteng ini dikenal dengan sebutan Klenteng Couw Su Kong. Tidak
jauh dari klenteng ini terdapat makam Dewi Neng yang merupakan
makam keramat. Menurut tradisi setempat Dewi Neng adalah seorang
wanita pribumi yang banyak jasanya terhadap pembangunan Klenteng
Couw Su Kong. Hal itulah yang menjadikan makam ini sering diziarahi
oleh orang-orang Cina peranakan yang banyak bekerja sebagai petani,
terutama di daerah Cibinong.
Dalam penyebaran dan pembauran itu, banyak orang Cina yang
bekerja sebagai petani, terutama di daerah Cibinong. Orang-orang
Cina ini dikenal dengan istilah “Cina Teko”, yakni orang-orang Cina
peranakan yang diusir oleh kompeni Belanda dari Batavia. Ada juga
istilah “Cina Robek”, yakni orang keturunan Cina yang masuk agama
Islam bukan karena keimanan, tetapi untuk menghindarkan diri dari
pajak kepala dan hal lain agar mereka mendapat perlindungan.
Akibat pembauran antara orang-orang Cina dan pribumi juga
berimbas pada adanya saling pengaruh-mempengaruhi antara
mereka. Sebut saja—pembauran kesenian pribumi dengan kesenian
orang Cina. Orang Cina turut mengembangkan seni musik gambang
kromong. Mereka memasukkan unsur musik tehyan, kongahyan, dan
sukong dalam musik gambang kromong. Tidak sedikit dari mereka
yang menjadi pendukung aktif sebagai senimannya. Dari kaum orang
Cina inilah, musik gambang kromong memperoleh sentuhan unsur
pribumi seperti musik gambang, kenong, kecrek, gendang, dan
sebagainya. Demikian pula dengan cerita-cerita rancagan yang
dibawakan dalam pertunjukan gambang rancag. Secara perlahan
tampak kadar pengaruh Cina dalam lagu dan lirik rancag serta orkes
gambang kromong semakin hari semakin berkurang. Kejadian ini
sama seperti musik tanjidor yang dikembangkan oleh orang Eropa
yang lama kelamaan menjadi musik pribumi dan dikenal sebagai
musik tradisi Betawi.
Semakin melemahnya pengaruh Cina terhadap perkembangan
orkes gambang kromong yang mengiringi gambang rancag juga
ditopang oleh hadirnya seniman pribumi seperti penyanyi legenda
66
Benyamin Sueb, Ida Royani, Lilis Suryani, Ritta Zahra, Herlina Efendi
dan sebagainya. Keadaan ini membuat lagu-lagu dan iringan musik
gambang kromong semakin dekat di telinga orang-orang pribumi
sehingga musik gambang kromong lama kelamaan menjadi ciri musik
orang pribumi, terutama masyarakat Betawi. Hal penunjang lainnya—
dari perubahan tersebut adalah sentuhan cerita-cerita yang dahulu
berbau cerita dari kalangan orang Cina, seperti Sam Pek Eng Tai, yakni
roman Cina klasik yang sangat digemari pada saat itu, termasuk cerita
Pho Sie Lie Tan, yaitu cerita tentang suka duka seorang putra raja Cina
zaman dahulu.
Kaitan antara kesenian gambang rancag dengan orkes gambang
kromong menurut Japp Kunst (1934, hlm. 308; dalam Ruchiat 1981,
hlm. 1) ditandai oleh peranan orang-orang Cina yang berhasil
memasukkan unsur musik mereka yang diselaraskan dengan musik
kaum pribumi. Perpaduan lainnya yang juga dilakukan dengan
memasukkan lagu-lagu Cina, seperti Sipatmo, Kongjilok, Phopantaw,
Citnosa, Macutay, Cutaypan dan sebagainya. Sementara lagu-lagu
pribumi yang biasa turut dimainkan dalam musik gambangkromong
untuk selingan dalam pertunjukan gambang rancag, seperti lagu-lagu
Jali-jali, Persi, Surilang, Bale-Bale, Lenggang Kangkung, Gelatik
Nguknguk, Onde-Onde dan sebagainya. Menurut data dari Yayah Andi
Saputra (2009) bahwa:
sejak tahun 1911, di Toko Djin Vich dan Co (Loa Yoe Djin) di daerah Pancoran, Batavia, menjual macam-macam versi atau judul rancag, antara lain: (1) Rancag Roemah Angoes Besar di Maoek, (2) Rancag Sie Mioen, (3) Rancag Nona Boedjang, (4) Rancag Orang Maen Kartoe, (5) Rancag Pak Baira di Tambun, (6) Rancag Si Pitoeng, (7) Rancag Entjek A Kiong Mati Dibunuh, (8) Rancag Orang Bersobat dengan Komedi Bangsawan, (9) Rancag Orang Dimadu, (10) Rancag Orang Derep Kelaboe, (11) Rancag Patima Mati Diboenoe, (12) Rancag Tukang Ketjot di Betawi, (13) Rancag Anak Ajem, (14) Rancag Sang Kodok, (15) Rancag Roepa-Roepa Burung, (16) Rancag Djago Si Angkrik, (17) Rancag Pak Tjenteng Soekain Mantoenya, (18) Rancag Di Buih Ponya Sengsara, (19) Rancag Tukang Sado Ditjela-tjelain.
67
Dari ke-19 lagu rancag tersebut sampai sekarang yang masih
biasa dibawakan adalah Rancag Si Pitoeng dan Rancag Djago Si
Angkrik, sementara rancag lainnya setelah tahun 1970-an sudah
jarang dibawakan.
Menurut sejarah dan catatan Japp Kunst (1934, hlm. 308)
diungkapkan bahwa “sekitar abad ke XIX dan awal abad XX
rombongan-rombongan orkes gambangkromong biasanya dimiliki
oleh cukong-cukong golongan Cina peranakan.” Di kalangan seniman
gambang kromong, para cukong dikenal dengan istilah “tauke”. Para
cukong itulah yang menanggung segala biaya, termasuk berbagai
kebutuhan anggota-anggotanya. Bahkan ada pula yang menyediakan
perumahan khusus bagi anak buahnya, istilah ini biasa disebut “bapak
angkat” seniman-seniman gambang kromong. Budaya kepemilikan
anak buah atau anak angkat grup musik adalah salah satu peninggalan
sistem perbudakan yang pernah berlaku di Indonesia. Sistem
perbudakan ini berakhir pada pertengahan abad XIX. Sistem
perbudakan pada masa itu dianggap dapat mengangkat status
keluarga dengan pemikiran semakin banyak budak semakin tinggi
status sosial seseorang—ditentukan oleh jumlah kepemilikan budak.
Para pemilik rombongan biasanya menerima “uang tanggapan”,
yaitu pembayaran dari yang menanggap kesenian mereka. Pada
umumnya orkes gambang kromong disajikan oleh golongan
masyarakat Cina peranakan dalam rangka memeriahkan berbagai
pesta, misalnya pesta perkawinan. Pada kesempatan-kesempatan
demikian orkes gambang kromong digunakan untuk mengiringi
nyanyian dan tarian yang biasa disebut Cokek. Rombongan gambang
kromong dengan cokek-cokeknya biasa disebut Wayang Cokek. Para
undangan ikut menari berpasangan dengan Cokek yang dalam istilah
setempat disebut ngibing. Informan dalam wawancara tanggal 12
Oktober 2013, Ruchiat (86 tahun), menegaskan bahwa acara demikian
merupakan atraksi utama dari para buaya-buaya ngibing pada masa
itu, bahkan sampai dewasa ini. Budaya ngibing ini pada akhir tahuan
1990-an dan awal 2000-an masih bisa kita saksikan di sekitar wilayah
68
Cileungsi dan sekitarnya, terutama di Jalan Raya Narogong—di daerah
Pangkalan 5, Pangkalan 9, dan Pangkalan 12.
Pada acara-acara tertentu, misalnya pada pesta keluarga dengan
undangan terbatas tanpa diadakan tarian, orkes gambang kromong
biasanya digunakan untuk mengiringi cerita yang dinyanyikan.
Ceritanya dibawakan dalam bentuk syair atau pantun. Kebanyakan
cerita yang dibawakan adalah dalam bahasa Melayu yang umumnya
berupa cerita-cerita tentang berbagai peristiwa yang pernah terjadi
dan mengesankan seperti cerita Angkri, Pitung, Keramat Karem dan
sebagainya. Dalam wawancara tanggal 12 Oktober 2013, Ruchiat (86
tahun) menegaskan bahwa “cara penyajian rancagan disertai dengan
acting teater yang cukup memikat hati para penggemarnya.
Pertunjukan demikian itu, yakni hadirnya orkes gambang kromong
mengiringi nyanyian syair atau pantun cerita disebut gambang rancag.
Syair atau pantun yang dinyanyikan disebut rancagan. Menyanyikan
atau berpantunnya disebut ngerancag.
Sebagai salah satu bentuk teater bertutur (istilah yang dilansir
pada akhir tahun 1980), pertunjukan gambang rancag dititikberatkan
pada cara pembawaan cerita dan pada musiknya. Ada pendapat yang
menyatakan tidak mustahil bila Lenong, salah satu teater Betawi,
merupakan kelanjutan dari teaterisasi gambang rancag. Hal ini
tentunya perlu mendapat penelitian yang lebih lanjut.
Menurut Japp Kunst—seorang etnomusikolog Belanda, pada
tahun 1930-an abad ini kehidupan gambang rancag sebagai
pertunjukan terbilang masih cukup baik, dalam arti masih cukup
banyak dipergelarkan sebagai pertunjukan panggilan. Hal ini
didukung oleh tulisan Japp Kunst yang banyak menulis tentang musik
dari berbagai suku di Indonesia. Dalam salah satu bukunya De
Toonkunst van Java yang diterbitkan pada tahun 1934 mengenai
musik khas Betawi, bentuk pertunjukan gambang digambarkan
sebagai salah satu waditranya. Lebih jelas lagi Japp Kunst (1934, hlm.
308) mengatakakan bahwa:
orkes gambang kromong, terutama di Batavia dan daerah sekitarnya yang memperoleh pengaruh Cina, digunakan untuk
69
mengiringi cerita-cerita yang dinyanyikan (apa yang disebut syair) tentang kejadian-kejadian mengesankan yang terjadi pada tahun-tahun silam, misalnya cerita Si Pitung Rampok Betawi, cerita Angkri Digantung di Betawi, cerita Delep Kelebu di Laut, dengan lagu-lagu seperti Jali-Jali, Persi, Surilang, Lenggang Kangkung, Kramat Karem dan sebagainya, dengan diiringi alat musik yang terdiri dari gambang kayu, kenong, dan gendang.
Selanjutnya pengungkapan musik spesifik Betawi yang
berikutnya adalah seperti yang terdapat dalam wayang cokek, yaitu
nyanyian dan tarian yang dilakukan oleh wanita-wanita (berasal dari
budak-budak). Pada kesempatan demikian rambut mereka dikepang
serta mengenakan baju kurung, Orkesnya terdiri dari gambang kayu,
rebab, suling, dan kempul, kadang-kadang ditambah dengan kenong,
ketuk, kecrek, dan gendang. Dalam nyanyian sering terdengar kata-
kata: Si nona disayang dan Si Baba disayang, artinya Nyonya kusayang,
Tuanku sayang.
Dari tulisan Kunst (1934, hlm. 308) dapat ditarik kesimpulan
bahwa kehidupan gambang rancag pada waktu itu tidak tertinggal
popularitasnya dengan wayang cokek. Dengan kata lain, kalaupun
tidak lebih menonjol maka sekurang-kurangnya tidak terlalu jauh
kedudukannya dari wayang cokek di kalangan penggemarnya.
Entong Dele (55 tahun) mengungkapkan bahwa: juru rancag
Cina peranakan yang terkenal sekitar tahun 1930-an antara lain Kho
Cin Pek, seorang tunanetra dari Petak Sembilan, dan Kucai dari
Cileungsi. Pada zaman dahulu, kedua orang itu dianggap paling mahir
membawakan syair Pho Sio Lio Tan, Sam Pek Eng Tay, dan cerita-cerita
lainnya. Sementara perancag pribumi yang paling terkenal Pa Ji’an dan
Pa Ji’in dari Bojong Gede. Pa Ji’an dan Pa Ji’in mahir dalam memikat
hati penontonnya. Dalam wawancara tanggal 12 Oktober 2013,
Ruchiat (86 tahun) menegaskan bahwa:
menurut Tanu TRH yang berulang kali pernah menonton pertunjukan gambang rancag oleh perancag Pa Ji’an dan Pa Ji’in, jika kedua perancag tersebut sedang membawakan nyanyian rancag—atau menceritakan hal ihwal Si Pitung, Si Angkri, atau tentang Keramat Karem dan kisah-kisah yang lain dengan suara
70
serak-serak basah, para penonton seakan-akan terkesima. Mereka akan menahan nafas karena khawatir ada kata-kata yang luput dari pendengaran mereka.
Sementara itu mengenai kemunduran popularitas kesenian
gambang rancag, Japp Kunst (1934, hlm. 308) mengungkapkan
bahwa:
ketika kesenian gambang rancag mulai menurun popularitasnya dan kedudukannya di tengah masyarakat yang disebabkan oleh berbagai hal, baik yang bersifat internal maupun eksternal, penyebab kemundurannya dimungkinkan karena gambang rancag dianggap musik jalanan murahan karena pada waktu itu sudah banyak gambang, yaitu rombongan yang mengadakan pertunjukan keliling sepanjang jalan dari rumah ke rumah atau dikenal dengan istilah ngamen.
Keadaan ini rupanya sebagai salah satu akibat berantai dari
krisis ekonomi yang pada saat itu melanda seluruh dunia akibat
Perang Dunia I yang dilanjutkan dengan mengganasnya “Zaman
Malayse” atau “Zaman Meleset”, menurut lidah rakyat pribumi. Pada
zaman itu, pemerintah Hindia Belanda memerintahkan rakyat atau
kaum pribumi untuk menghemat keuangan. Mereka bahkan menakar
biaya hidup satu orang bangsa Indonesia cukup dengan segobang (dua
setengah sen) per hari. Dalam situasi perekonomian yang sulit itu
tidak ada lagi cukong-cukong Cina yang bersedia menjamin
penghidupan rombongan gambang kromong sebagai bapak angkat,
ditambah dengan semakin jarangnya orang yang menanggap.
Peristiwa kedua yang berimbas pada eksodus besar-besaran
orang Cina dan keturunan untuk kembali ke Cina, disebabkan oleh
keluarnya Peraturan No. 10 Tahun 1959 yang berisi larangan orang
asing termasuk orang Cina untuk memiliki usaha di bidang
perdagangan eceran di tingkat kabupaten (di luar ibu kota daerah)
dan wajib mengalihkan usaha mereka kepada warga Negara
Indonesia. Peraturan ini menjadi kontroversial sehingga memakan
korban jiwa orang-orang Cina—yang dikenal dengan peristiwa
“kerusuhan rasial Cibadak”. Sebagian besar orang Cina dan keturunan
menjadi ketakutan dan pergi meninggalkan Indonesia. Akibat
71
peristiwa itu, banyak peralatan kesenian milik Tauke atau orang tua
angkat yang menjamin hidup seniman pribumi, berpindah tangan.
Pada saat itu peralatan musik orang-orang Cina umumnya diserahkan
kepada pembantu atau anak angkat mereka. Dalam wawancara
tanggal 11 Januari 2014, Rojali (78 tahun) menegaskan bahwa “salah
satu contohnya adalah Engkong Samad—mertua Rojali, yang pada
peristiwa itu juga mendapat limpahan peralatan musik gambang
kromong dari tuannya karena terpaksa harus pergi ke negara asal
mereka di Tiongkok untuk menyelamatkan diri.”
Sepeninggal tuan-tuan seniman itu, keadaan kehidupan serba
sulit menghinggapi berbagai kesenian rakyat, termasuk rombongan
gambang rancag dalam kelompok gambang kromong sehingga harus
menjelajahi pelosok-pelosok kota Jakarta dan sekitarnya untuk
mengadakan pertunjukan dari rumah ke rumah—ngamen. “Hal ini
dilakukan untuk mendapatkan Congin-Nongin”, menurut Amshar (55
tahun), salah satu seniman gambang rancag yang pernah
mengalaminya.
Pengaruh gambang rancag pada lenong tampak pada kebiasaan
adanya rancagan pada saat-saat tertentu, misalnya pada waktu
sebelum cerita atau tontonan inti dimulai dalam pertunjukan lenong.
Maksudnya, lenong yang masih mengikuti tradisi, memiliki kebiasaan
atau konvensi bahwa sebelum cerita dimulai biasa didahului dengan
ucapan perkenalan yang dinyanyikan, dengan diiringi lagu Persi.
Dalam penyampaian alur cerita pada pertunjukan lenong sering
pula terdengar pantun-pantunan, bahkan tidak jarang pada saat-saat
yang tegang. Misalnya pada waktu seorang tokoh jagoan berhadapan
dengan lawannya. Sebagai contoh di sini diambilkan dari pementasan
Lenong Setia Kawan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada
tanggal 5 Maret 1978.
Di situ kentang di sini kentang; Kentang sepikul dibagi dua; Di situ nantang di sini nantang; Lu mukul gua sedia.
72
Pantunan tersebut kemudian dijawab oleh lawannya juga
dengan pantunan. Seperti Samad Modo, Entong Dale, Amsar, Romo
Root yang merupakan survival kesenian Betawi, dewasa ini mereka
berkecimpung dalam lenong dan wayang cokek. Panggilan untuk
ngerancag sudah sangat jarang, bahkan dapat dikatakan sama sekali
tidak ada. Sedangkan ngamen, sejak adanya larangan dari yang
berwajib mulai tahun 1950-an memang sudah tidak dilakukan lagi.
Tanpa pembinaan intensif dan terarah, dikhawatirkan gambang
rancag, salah satu bentuk pertunjukan khas Betawi, dalam waktu yang
tidak lagi lama akan punah. Oleh karena itu, harus ada upaya aktif dari
masyarakat dan pemerintah untuk terus melakukan pertunjukan dan
penelitian terhadap bagaimana upaya mengembangkan pertunjukan
gambang rancag. Hal yang paling utama jika ingin gambang rancag
tetap eksis harus ada apresiasi masyarakat. Dalam wawancara 12
Desember 2013, Ruchiat (86 tahun)—Tokoh seni tari Betawi
menyatakan bahwa “bagaimanapun kuatnya bantuan pemerintah
dalam pengembangan dan pemberdayaan kesenian gambang rancag,
tidak berarti apa-apa jika sudah tidak ada apresiasi masyarakat
terhadap keberlanjutan kesenian gambang rancag.” Penjelasan
Ruchiat tersebut menunjukkan bahwa keadaan gambang rancag di
masyarakat sudah hampir punah. Hal ini terlihat dari berkurangnya
tanggapan hajatan yang diperoleh langsung dari masyarakat. Saat ini
masyarakat cenderung lebih memilih untuk menanggap organ tunggal
daripada kesenian gambang rancag atau kesenian Betawi lainnya.
Alasan mereka sederhana, selain lahan untuk panggung di masyarakat
hampir habis, juga faktor biaya menanggap gambang rancag lebih
mahal dari organ tunggal.
Gambaran di atas adalah selayang pandang gambang rancag di
masa lalu. Untuk lebih jelas bagaimana ihwal gambang rancag
sekarang berikut akan diuraikan beberapa pertunjukan gambang
rancag di DKI Jakarta dan sekitarnya yang telah diamati oleh penulis
sejak tahun 2010 sampai tahun 2014.
Ciri gambang rancag Menurut Ruchiat dkk, (2003, hlm. 150)
bahwa bercirikan nyanyian yang dipantunkan, disebut cerita
73
rancagan, atau cukup disebut rancag atau rancak berbentuk pantun
berkait.” Jadi, bisa dikatakan gambang rancag adalah musik gambang
kromong disertai nyanyian yang menuturkan cerita-cerita rakyat
Betawi dalam bentuk pantun atau syair dan dibumbui oleh lawakan
atau humor. Cerita yang dibawakan dengan dipantunkan disebut
cerita rancag, yang berbentuk pantun berkait dan syair. Berikut
adalah contoh rancagan yang berbentuk pantun berkait, yaitu Rancag
Si Ankri, Jago Pasar Ikan, yang pernah dibawakan Rojali alias Jali Jalut
(78 Tahun) dan Samad kelompok Jali Putra Pekayon Gandaria pada
tahun 1980.
1. a Ketik kenari cabang patah;
pasang kuping biar terang;
rancag si Angkri punya cerita;
belum lama jadi jago, satu peti mencuri barang.
1. b Ketik kenari cabang patah;
ambil papaya di petuakan;
si Angkri punya cerita;
buayanya di pasar ikan.
Pantun pada rancag disusun secara improvisasi mengikuti jalur
cerita yang sudah tetap. Suatu cerita dapat dipanjangkan penyajiannya
dengan berbagai tambahan. Sebagai contoh penyajiannya yaitu
dengan lawakan yang sering kali menyimpang dari cerita, tetapi tetap
disenangi penontonnya. Rancag juga biasa disajikan dengan iringan
orkes gambang kromong atau dengan sebutan gambang rancag.
Kemudian, pagelaran atau pertunjukan gambang rancag dilakukan
oleh dua orang atau lebih juru rancag yang menceritakan dengan
dinyanyikan dan diiringi orkes gambangkromong. Sejak awal gambang
rancag dipentaskan tanpa panggung. Tempat pementasan sejajar
dengan penonton yang berada di sekelilingnya. Jadi, gambang rancag
ini bentuk penyajiannya meliputi pertunjukan yang lengkap dengan
iringan orkes dan nyanyian.
Saputra (2009, hlm. 8) mengemukakan bahwa “gambang rancag
bisa disebut sebagai pertunjukan musik sekaligus teater, bahkan
sastra. Pertunjukannya terdiri dari dua unsur, yaitu gambang dan
74
rancag, gambang berarti musik pengiringnya dan rancag adalah cerita
yang dibawakannya dalam bentuk pantun berkait. Tokoh dalam
pantun berkait itu pada umumnya berupa lakon-lakon jagoan, seperti
Si Pitung, Si Jampang, dan Si Angkri. Pantun berkait ini dinyanyikan
oleh dua orang bergantian seperti berbalas pantun, sehingga
pertunjukan gambang rancag menyerupai pertunjukan musik yang
dilengkapi dengan teater dan unsur sastra dalam menyajikannya.
Pada pagelaran atau pertunjukan gambang rancag selalu terbagi
atas tiga bagian, bagian pembukaan yang diisi dengan lagu-lagu phobin
yang berfungsi mengumpulkan penonton. Bagian kedua diisi dengan
penampilan lagu-lagu hiburan atau lagu sayur yang berfungsi sebagai
selingan sebelum ngerancag dimulai. Lagu pada bagian kedua ini sama
dengan lagu yang dibawakan dalam orkes gambang kromong. Bagian
ketiga diisi dengan lagu rancak atau rancag, sementara irama
musiknya adalah instrumen dendang Surabaya, Gelatik, Ngaknguk,
Persi, Phobin Jago, Phobin Tintin, dan Phobin Tukang Sado. Sebagai
pemain rancag bukan saja harus bisa bernyanyi, tetapi juga dapat
menyusun pantun secara improvisasi, ingat jalan cerita yang akan
dibawakan, dan harus ingat lakon-lakon yang dimainkan. Berikut
adalah cuplikan rancag Si Pitung.
Ambil simping alasnya kerang; Pasang pelita terang digantung; Pasang kuping nyatalah biar terang; Di gambang rancag buka rancag jago Bang Pitung.
Pada tahun dua puluhan ada seorang juru rancag yang terkenal
bernama Jian, seorang tuna netra yang memiliki suara serak-serak
basah. Menurut informasi orang Betawi, apabila ia sedang berpantun
menceritakan tokoh Si Pitung atau tentang Keramat Dalem dengan
iringan musik gambang kromong irama lagu Parsi, umumnya para
penonton seakan-akan menahan nafas karena khawatir ada kata-kata
yang luput dari pendengarannya (Ruchiat, 2003, hlm. 166). Tokoh
rancag yang pernah ada, misalnya: Samad Modo bersama Rojalialias
Jali Jalut di Pekayon, Entong Dale bersama Bedeh di Cijantung Jakarta
Timur, dan Amsar bersama Ali di Bendungan Jago Jakarta Pusat.
75
Sama halnya dengan sebuah pertunjukan, gambang rancag
memiliki unsur-unsur pertunjukan. Unsur-unsur dalam pertunjukan
gambang rancag meliputi pemain, pemusik, musik, cerita, dan
penonton. Pemain adalah orang yang merancag atau menyanyikan
pantun berupa cerita yang diiringi oleh musik gambang—musik
tersebut dimainkan oleh pemusik, terdiri dari gambang, gong, kecrek,
tehyan, kongayan, dan lain-lain. Pertunjukan ditonton oleh penonton
dalam suasana yang sesuai konteks acara. Fungsi gambang rancag
yang ditentukan oleh masyarakatnya tentu perlu ditanamkan kepada
masyarakat pendukungnya agar tradisi ini tetap hidup di tengah
masyarakat Betawi. Dengan demikian, baik pemain maupun unsur
lainnya sama-sama berpengaruh besar bagi pertunjukan gambang
rancag.
Dari pendapat di atas dapat dibedakan pengertian gambang
rancag dengan gambang kromong. Gambang rancag, menurut Ruchiat
(2003, hlm. 156) adalah “pertunjukan lagu rancag (berupa cerita Si
Pitung, Si Angkri, Si Jampang, Si Conatdan sebagainya) yang diiringi
musik gambang (gambang kromong). ”Hal ini seperti yang telah
diuraikan di atas. Sementara Kleden (1996, hlm. 51) mengemukakan
bahwa “orkes gambang kromong merupakan jenis musik untuk
mengiringi pertunjukan lagu-lagu kombinasi yang tidak hanya terdiri
dari gambang dan kromong saja tetapi juga disertai orkes Melayu dan
orkes dangdut.”
Kedua pendapat di atas jelas telah membedakan batasan dari
jenis seni Betawi ini. Gambang rancag lebih kuat pada unsur
sastranya, sedangkan gambang kromong lebih kuat unsur seni
musiknya. Oleh karena itu, untuk lebih mengetahui unsur pembentuk
tradisi lisan gambang rancag, perlu digambarkan bagian-bagian dalam
pertunjukan tradisi lisan gambang rancag.
Menurut Sopandi dkk. (1999, hlm. 28) gambang rancag
memiliki aspek-aspek seni, yaitu: 1) musik, 2) sastra, 3) seni rupa, 4)
teater (senggakan), 5) bodor, dan 6) pemanggungan. Berikut akan
diuraikan beberapa aspek penting dalam tradisi lisan gambang rancag
tersebut. Musik, yaitu meliputi: a) tangga nada, b) irama/birama, c)
76
fungsi iringan, d) instrumen, dan e) lagu-lagu. Tangga nada adalah
susunan nada yang disusun berurutan, baik naik maupun turun
dimulai dari suatu nada hingga ulangannya, baik pada oktaf kecil
maupun oktaf besar dengan jumlah nada dan interval tertentu. Tangga
nada yang digunakan adalah tangga nada pentatonik, meliputi tangga
nada mayor dan tangga nada minor, serta tangga nada grigorian.
Irama/birama/maat dalam aspek gambang rancag dapat didefinisikan
sebagai berikut. Pertama, istilah maat adalah ukuran waktu yang
digunakan untuk menyajikan bar/mistura dari suatu lagu. Kedua, maat
adalah pergantian antara tekanan ringan dan tekanan berat secara
teratur dalam tiap-tiap bar/gatra.
Selanjutnya gambang rancag dapat dimaknai sebagai sebuah
representasi identitas, seperti dalam bentuk kearifan lokal dan mitos
masyarakat Betawi. Dari segi kearifan lokal tampak dari bentuk
pertunjukan sebagai wadah untuk bersilaturahmi keluarga. Selain itu
bentuk kearifan lokal juga didapat dari rumah yang digambarkan
dalam cerita sebagai tempat si Pitung merampok, yaitu rumah juragan
Haji Syamsudin. Rumah tersebut sampai sekarang masih berdiri
kokoh sebagai cagar budaya Betawi yang mewujudkan sebuah
kearifan lokal masyarakat Betawi. Berdasarkan cagar budaya tersebut,
masyarakat Betawi dapat memaknainya sebagai sebuah bentuk yang
menandai perlawanan orang Betawi terhadap kezaliman kekuasaan
Belanda pada awal tahun 1800-an. Tokoh Pitung dianggap oleh
masyarakat Betawi sebagai pahlawan sebab telah membantu rakyat
Betawi dari kekejaman pihak Belanda dan tuan-tuan tanah sebagai
kaki tangan Belanda.
Selanjutnya gambang rancag juga dimaknai sebagai simbol
mitos, hal ini digambarkan dalam teks rancag bahwa Pitung hanya
bisa mati jika ditembak dengan peluru emas. Teks ini dibuat sebagai
bentuk representasi identitas oleh masyarakat Betawi kalau Pitung
memiliki ilmu yang tinggi, karena hanya bisa mati jika ditembak
menggunakan peluru emas hingga membuat Sekot Hena
mempersiapkan segala bentuk untuk bisa menangkap si Pitung. Mitos
Pitung hanya bisa mati ditembak peluru emas adalah bentuk
77
representasi identitas masyarakat Betawi yang diproduksi oleh orang
Betawi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai masyarakat yang
dianggap terbelakang, pendidikan rendah, terusir dari tanahnya
sendiri yaitu Batavia, maka kehadiran Pitung merupakan bentuk
perlawanan dengan penggambaran sosoknya yang memiliki berbagai
kekuatan ilmu yang tidak tertandingi. Bahkan meskipun lawannya
adalah Sekot Hena (Kepala Polisi di Batavia), ternyata Sekot Hena juga
gentar menghadapi Pitung.
Fungsi dari penulisan ini juga dapat memberikan kontribusi
terhadap ilmu pengetahuan secara teoretis dalam memecahkan
masalah penelitian. Di samping itu, dapat memberikan kontribusi
praktis dari aspek manajemen dengan menyajikan berbagai kebijakan
dari temuan yang dihasilkan. Kedua kontribusi tersebut berimplikasi
secara langsung terhadap perkembangan gambang rancag dari segi
kuantitas dan kualitas. Perkembangan dari segi kuantitas berimplikasi
terhadap meningkatnya jumlah perancag di DKI Jakarta melalui
kegiatan pelatihan gambang rancag yang dilakukan, di lima wilayah
DKI Jakarta, misalnya Balai Latihan Kesenian (BLK ) Jakarta Timur,
BLK Jakarta Utara, BLK Jakarta Pusat, BLK Jakarta Selatan. Materi yang
diberikan dalam pelatihan adalah materi pengenalan pertunjukan
gambang rancag, materi pemahaman lagu-lagu rancag, dan materi
penguasaan musik yang mengiringi perancag ketika sedang
melakukan pertunjukan gambang rancag. Setelah itu mereka
diarahkan oleh para panitia dan narasumber pelatihan gambang
rancag yang berasal dari ahli atau pemain gambang rancag yang
selama ini mahir memainkan pertunjukan gambang rancag sebagai
seniman gambang rancag tujuan dari pelatihan gambang rancag agar
semua peserta dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan
bagaimana cara melakukan pertunjukan gambang rancag agar dapat
dimasukkan dalam kegiatan pelatihan. Dari pertunjukan gambang
rancag sebagai seni pertunjukan yang merupakan karakter
masyarakat Betawi ditunjukkan melalui cara perancag membawakan
lagu rancag dengan bentuk humoris dan terbuka yang menunjukkan
sikap orang Betawi sebagai masyarakat egaliter. Karakter lain dalam
78
pertunjukan gambang rancag menunjukkan adanya penghormatan
terhadap tokoh yang diceritakan sebagai tokoh pahlawan Betawi,
misalnya dengan membawakan cerita si Pitung. Si Pitung adalah
simbol perlawanan masyarakat Betawi dari tekanan tuan tanah di
daerah Partekelir dan tekanan kolonial belanda. Pada saat itu hadir
tokoh si Pitung sebagai tokoh hero yang memberi pertolongan kepada
rakyat Betawi yang mengalami penindasan ganda baik dari kolonial
Belanda maupun dari para tuan tanah. Hal inilah yang menjadi
kerinduan orang Betawi terhadap cerita pahlawannya diceritakan
melalui pantun dan syair gambang rancag.
Selanjutnya akan digambarkan karakter perkampungan budaya
Betawi melalui pertunjukan gambang kromong,
D. Pertunjukan Gambang Kromong
Gambang kromong diambil dari nama dua alat musik, yaitu dua
jenis alat perkusi, yakni gambang dan kromong. Gambang terbuat dari
sejumlah bilah 18 buah yang terbuat dari kayu suangking, huruf batu
atau jenis kayu lain yang empuk bunyinya jika dipukul. Sementara
kromong dibuat dari perunggu atau besi, berjumlah 10 buah (10 “10
pencon”). Jenis musik ini adalah perpaduan dari unsur pribumi dan
Cina. Pada alat musik gesek didominasi dari Cina, yaitu tehyan,
kongahyan, dan sukong. Sedangkan alat musik yang lainnya, yaitu,
gambang, kromong, gendang, dan kecrek berasal dari musik pribumi.
Perpaduan kedua unsur kebudayaan tersebut tampak pula pada
perbendaharaan lagu-lagu yang dibawakan dalam pertunjukan musik
gambang kromong. Lagu-lagu gambang krong yang diadaptasi dari
budaya pribumi seperti, Jali-Jali, Surilang, Persi, Balo-Balo, Lengggang-
Lenggang Kangkung, Onde-Onde, Gelatik Nguknguk dan sebagainya.
Sedangkan lagu-lagu yang bercorak Cina seperti, Kong Jilck, Sipatmo,
Phe Pantaw, Citnosa, Macuntay, Gutaypan dan sebagainya.
79
Gambar 4. Penyanyi Gambang Kromong, Kamis, 29 Juni 2017
Dok. Pribadi
Sejarah gambang kromong menurut tulisan Phoa Kian Sie dalam
Ruchiat (2013: 20) bahwa orkes gambang kromong merupakan
perkembangan dari orkes Yang Khim yang terdiri atas Yang-Khim,
Sukong, Hosiang, Thehian, Kongahian, Sambian, Suling, Pan, (kecrek)
dan Ningnong. Karena Yang-Khim sulit diperoleh, ada inisiatif
menggantinya dengan gambang yang larasnya disesuaikan dengan
asalnya dari Hokkian. Sementara untuk Sukong, Tehian, dan
Kongahian tetap dipakai sebab dapat dibuat di sini. Alat yang
dihilangkan adalah Sambian dan Hosiang karena tidak terlalu
mengurangi nilai penyajian musiknya.
Adanya pembauran musik pribumi dan Cina menyebabkan
musik gambang kromong digemari oleh masyarakat, baik pribumi
maupun keturunan. Hal ini tentu dilatarbelakangi oleh adanya proses
inkulturasi budaya yang begitu serasi antara pribumi dan Cina. Tak
heran jika komunitas atau grup-grup pertunjukan gambang kromong
sering mengisi acara keramaian di masyarakat kampung atau orang
pribumi maupun di acara-acara masyarakat Cina, misalnya pada
80
perayaan Cap Gomeh di beberapa wilayah di DKI Jakarta dan
Sekitarnya, grup gambang kromong sering diundang atau ditanggap.
Musik Gambang krong sejak tahun 1880 menurut Ruchiat
(2013: 20) bahwa atas usaha TanWangwe dengan dukungan Bek
(Wijk Meester) Pasar Senen Tang Tjoe, orkes gambang mulai
dilengkapi dengan Kromong, Kempul, Gendang dan Gong. Lagu-lagu
yang dipilih lagu—lagu Sunda popular, sebagaimana ditulis oleh Phe
Kian Sio sebagai berikut:“Pertjobaan Wijk Meester Teng Tjoe telah
berhasil lagoelagoe gambang ditaboeh dengan tambahan alat tersebut
diatas membikin tambah goembira Tjo Kek dan pendengar-
pendengarnya . Dan Moelai itoe waktoe lagoe-lagoe Soenda banyak
dipake oleh orkes gambang. Djoega orang moelai brani pasang
slendang boeat “mengibing”.
Gambaran sejarah di atas dapat dikatakan bahwa awal mulainya
musik gambang kromong dikenal oleh masyarakat pribumi. Adanya
keberanian untuk mengolaborasikan dua budaya musik pribumi dan
Cina. Dulunya musik orkes gambang kromong hanya dimainkan dalam
lingkungan keluarga Cina, sejak saat itu jenis musik ini mulai sering
diminati dan ditanggap oleh orang pribumi apalagi jika ada keramaian
untuk mengiringi pertunjukan musik gambang kromong. Dan
mencapai puncaknya setelah masa tahun 70-an, dengan ada beberapa
penyanyi Indonesia yang masuk dalam kelompok gambang kromong
seperti, Benyamin S., Ida Royani, Lilis Suryani, Herlina Effendi, dan
lain-lain.
Penyebaran gambang kromong di DKI Jakarta dan sekitarnya
adalah jenis musik yang paling merata. Menurut Data Penelitian
lapangan bahwa perkembangan musik Gambang Kromong FIB 2010
sampai sekarang menunjukkan bahwa hampir masyarakat yang
komunitasnya banyak Orang Cina maka perkembangan Gambang
kromong akan banyak grup yang tumbuh, seperti di daerah Jakarta
Utara dan Jakarta Barat, daripada daerah Jakarta Selatan dan Jakarta
Timur.
Pada perkembangan gambang kromong berdasarkan asli dan
kombinasi juga menjadi hal yang menarik. Jika gambang kromong
81
yang asli yaitu gambang kromong yang menggunakan alat musik yang
sesuai pakem, misalnya penggunaan alat musik yang sesuai dengan
awal terbentuknya istilah musik ini tahun 1880-an bahwa harus ada
musik gambang, kromong, gendang, kecrek, Tahiyan, Kongahyan,
Sukong. Sementara, musik gambang kromong yang kombinasi yaitu
musik yang sudah mendapat sentuhan alat-alat musik modern yang
kadang-kadang elektronik, seperti gitar melodi, organ, saxopone drum
dan sebagainya. Adanya perubahan dari laras pentatonis menjadi
diatonis tanpa terasa mengganggu. Adanya penambahan kombinasi ini
tidak menjadikan warna musik ini berubah justru dapat lebih mudah
diterima oleh telinga anak muda sekarang, masuknya musik
kombinasi ini juga diikuti oleh masuknya lagu-lagu pop Betawi secara
wajar, tidak dipaksakan, terutama bagi generasi muda tampaknya
gambang kromong kombinasi ini lebih komunikatif sekalipun kadang-
kadang kecenderungannya tersisihnya suara alat-alat gambang
kromong asli oleh alat musik elektronis yang semakin dominan.
Rombongan komunitas gambang kromong di DKI Jakarta dan
sekitarnya masih eksis, misalnya dimiliki oleh kelompok yang
dipimpin oleh orang pribumi ekonomi lemah, seperti Rombongan
Setia Hati pimpinan Amsar di Bendu gan Jago, Rombongan Putra
Cijantung pimpinan Marta (yang dulu dipimpin oleh Nyaat),
rombongan Haruda putih Pimpinan Samad Modo di Pekayon Gandaria
yang sekarang dipimpin oleh Jali Jalut (84 tahun) yang sekarang juga
diteruskan oleh Putranya Burhan (46 tahun) dan Firman (36 tahun).
Sedang gambang kromong kombinasi biasanya lebih dimiliki oleh
grup yang memiliki ekonomi lebih kuat, umumnya didominasi oleh
grup Cina, seperti Rombongan Naga Mas pimpinan Bhu Thian Hay
(Almarhum), Naga Mustika pimpinan Suryahanda, Selendang Delima
"Pimpinan Liem Thian Pi dan sebagainya. Dan informasi terakhir
bahwa keberadaan grup ini hampir sudah meninggal semua. Gambang
kromong di Setu Babakan pada perayaan Lebaran 2017 lalu yaitu
dipertunjukkan grup Bang Andi dengan musik gambang kromong
kombinasi. Pada saat itu dinyanyikan beberapa lagu seperti jail-jali.
82
E. Kesimpulan
Pertunjukan gambang rancag yang merupakan karakter hidup
masyarakat Betawi telah dilestarikan oleh komunitas Putra Jali
dengan berkolaborasi dengan pemain mudah yunior. Kelompok Putra
Jali mewariskan ilmu merancag dengan ara merancag bareng adalah
sebuah bentuk pengelolaan yang membuka pewarisan pada orang lain
di luar keluarga inti yang selama ini tertutup. Tujuan kolaborasi ini
sebagai bentuk penelitian untuk mendapatkan model karakter
perkampungan budaya Betawi berupa bentuk pengelolaan
pertunjukan yang mampu berkolaborasi dengan bintang komunitas
tradisi yang telah memiliki jam terbang, tujuannya saling memberi
pengalaman dan pengetahuan, termasuk penurunan atau pewarisan
pertunjukan yang berkarakter dengan cara bertukar ilmu dalam
pertunjukan antara pemain muda dengan senior.
Gambang kromong diambil dari nama dua alat musik, yaitu dua
jenis alat perkusi, yakni gambang dan kromong. Gambang terbuat dari
sejumlah bilah 18 buah yang terbuat dari kayu suangking, huru batu
atau jenis kayu lain yang empuk bunyinya jika dipukul. Sementara
kromong dibuat dariperunggu atau besi, berjumlah 10 buah (10 “10
pencon”). Jenis musik ini adalah perpaduan dari unsur pribumi dan
Cina. Pada alat musik gesek didominasi dari Cina, yaitu tehyan,
kongahyan, dan sukong. Sedangkan alat musik yang lainnya, yaitu,
gambang, kromong, gendang, dan kecrek berasal dari musik pribumi.
Perpaduan kedua unsur kebudayaan tersebut tampak pula pada
perbendaharaan lagu-lagu yang dibawakan dalam pertunjukan musik
gambang kromong. Lagu-lagu gambang krong yang diadaptasi dari
budaya pribumi seperti, Jali-Jali, Surilang, Persi, Balo-Balo, Lengggang-
Lenggang Kangkung, Onde-Onde, Gelatik Nguknguk dan sebagainya.
Sedangkan lagu-lagu yang bercorak Cina seperti, Kong Jilck, Sipatmo,
Phe Pantaw, Citnosa, Macuntay, Gutaypan dan sebagainya.
83
KARAKTERISTIK PERTUNJUKAN BUDAYA BETAWI
A. Pertunjukan Sahibul Hikayat
Sahibul hikayat adalah cerita-cerita yang berasal dari Timur
tengah, antara lain bersumber pada cerita Seribu Satu Malam, Alfu Lail
Wal lail. Istilah Sahibul Hikayat yang berarti yang empunya cerita.
Dalam Arab: Shohibul Hikayat yang berarti yang empunya cerita.
Dalam membawakan cerita sahibul hikayat juru hikayat sering
mengucapkan kata-kata: “Menurut sahibul hikayat”, atau kata “sahibul
hikayat”. Oleh karena itu, cerita-cerita kelompok ini biasa disebut
sahibul hikayat. Ucapan demikian itu digunakan untuk memberikan
tekanan kepada yang akan diceritakan selanjutnya, yang kadang-
kadang merupakan hal yang tidak masuk akal, contohnya sebagai
cuplikan berikut. “Jin itu menaruh anaknya di ayunan, Sembari nyanyi
di ayun, maksudnya supaya anaknya tidur. Kata Sohibul hikayat,
ayunan itu baru balik sembilan taun kemudian…” (Diambil dari salah
satu mata acara radio swasta). Dengan kata-kata sahibul hikayat itu
pertanggungjawaban diserahkan kepada yang empunya cerita, yang
entah siapa. Sahibul hikayat terdapat di daerah tengah wilayah
Budaya Betawi atau Betawi kota, antara Tanah Abang dengan
Salemba, antara Mampang Prapatan sampai Taman Sari.
Gambar 5. Pertun. Sahibul Hikayat, Kamis, 29 Juni 2017
Dok. Pribadi
84
Pembawa cerita sahibul hikayat, biasa disebut tukang cerita,
atau juru hikayat. Juru hikayat yang terkenal pada masa lalu, antara
lain haji Ja’far, Haji Ma’ruf kemudian Mohammad Zahid, yang terkenal
dengan sebutan “wak Jait”. Pakaian sehari-hari wak Jait selalu
mengenakan kain pelekat, berbaju potongan sadariah, berpeci hitam.
Juru hikayat biasanya bercerita sambil duduk bersila, ada yang sambil
memangku bantal, ada pula yang sekali-kali memukul gendang kecil
yang diletakkan di sampingnya, untuk memberikan aksentuasi pada
jalan cerita.
Sampai jaman Mohammad Zahid yang meninggal dalam usia 63
tahun, pada tahun 1993, cerita-cerita yang biasa dibawakan antara
lain Hasan Husin, Malakarma, Indra sakti, Ahmad Muhamad, Sahrul
Indra Laila bangsawan. Sahibul hikayat digemari oleh masyarakat
golongan santri. Dewasa ini biasa digunakan sebagai salah satu media
dakwah. Dengan demikian, sahibul hikayat menjadi panjang, karena
banyak ditambah bumbu-bumbu. Humor yang diselipkan di sana-sini
biasanya bersifat improvisatoristis. Kadang-kadang menyinggung-
nyinggung suasana masa kini. Setiap celah-celah dalam jalur cerita
diselipkan dakwah agama Islam. Seperti cerita rakyat lainnya, sahibul
hikayat bertema pokok klasik, yaitu kejahatan melawan kebajikan.
Sudah barang tentu kebajikan yang menang, sekalipun pada mulanya
tampak sengaja dibuat menderita kekalahan.
Sahibul hikayat yang berfungsi sebagai media dakwah seperti
yang dulu di pertunjukan oleh Mohammad Zaid, kini muncul kembali.
Pada perayaan lebaran Betawi di Setu Babakan, kata Zainuddin
kepada CNN Indonesia.com. Biasanya sahibul hikayat hanya digelar
sewaktu hajatan. Dalam pertunjukan ini, penonton akan menikmati
dongeng mengenai perjuangan agama, kisah para nabi, sampai kisah
mistis dari seorang penderita, yang disajikan dengan jenaka. “Orang
Betawi kan terkenal jenaka. Lewat perayaan Lebaran Betawi inilah,
kami coba sampaikan semangat untuk memelihara seni dan budaya
Betawi asli seperti sahibul hikayat kepada masyarakat,” katanya.
Penayangan sahibul hikayat pada Perayaan Lebaran Betawi 28
Juli 2017 lalu adalah bentuk kepedulian masyarakat Betawi melalui
85
Bamus Betawi untuk lebih dapat mengetahui bagaimana revitalisasi di
lakukan di Perkampungan Budaya Betawi, termasuk untuk lebih
mengetahui sahibul hikayat sebagai kebudayaan hibriditas, dan untuk
lebih mengenal bagaimana identitas budaya Betawi dalam tradisi
sahibul hikayat. Melalui cerita yang disampaikan secara berdakwa
diharapkan dapat menanamkan semangat cinta pada budaya lokal
Betawi.
Pertunjukan sahibul Hikayat yang digelar pada “Perayaan
Lebaran Betawi” tanggal 28 Juli 2017 lalu merupakan bentuk
revitalisasi sahibul hikayat, yaitu mengangkat kembali kesenian yang
mulai punah kepada keluarga besar Betawi di DKI Jakarta dan
sekitarnya. Revitalisasi sahibul hikayat yang dilakukan oleh BAMUS
Betawi sebagai upaya untuk mengingatkan kembali bahwa di Betawi
pernah ada kesenian yang digemari dan hidup di masyarakat kini ada
di hadapan mereka. Adapun cerita yang dipilih ketika perayaan
lebaran Betawi adalah lakon Hakim Siti Zulfah yang kini dibawakan
kembali Ustad Miptah. Adapun masyarakat yang menonton
pertunjukan Sahibul Hikayat malam itu, terdiri dari para panitia
Lebaran Betawi 2017 dari Bamus Betawi dibantu oleh UPK
Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan serta para penonton dari
lima wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
Pertunjukan sahibul hikayat sebagaimana layaknya atraksi
kesenian lainnya, dibawakan oleh pencerita, dalam hal ini sahibul
hikayat atau tukang cerita, sang pencerita harus mampu membawakan
cerita dengan kepiawaian dalam menciptakan cerita dengan cara
mengingat, apa yang diingat, diulang, diseru, dan ditegaskan oleh
penutur cerita, yaitu tradisi Betawi yang bermacam-macam bentuk
pengetahuannya yang tentu bisa diterima oleh masyarakatnya.
Adapun kutipan awal cerita yang dituturkan oleh sahibul hikayat.
Hakim Siti Zulfah
“Alkisah, ada Tuan saudagar kaya namanya Tuan saudagar Rosyad, biar dia kaya tapi pelit alias buntut gasiran. Orang kalo pelit, boro-boro surga, baunya aja kagak dapet. Uangnya banyak bukan dikasih ke Lebaran Betawi, bukan dia sumbang ke jalan Allah, tapi dia buang-buang ke jalan maksiat ke bar-bar, dan WTS
86
WTS untuk menghibur diri. Mobilnya 7 paling jelek CRV, setirnya racing, AC nya anyep (dingin), kalo meludah 5 menit jadi es. Bininya namanya Siti Zaenab, lagi hamil 3 bulan : Zaenab : “bang kemane aje sih bang, udah lebaran Betawi abang ngelayap mulu, saya takut anak kita jadi keturunan yang ga bener bang” sambil menangis…. Tuan Rosyad : “ Zaenab, ngomong sekali lagi gue tabok berdarah, abang banyak temen dimana-mana, bangsat!” jawab suami marah-marah sembari merokok. Zaenab (menangis makin jadi): “guwe nyesel kawin ama lu bang”. Suami (Tuan saudagar Rosyad) : “udah diem!!” lalu ambil kunci mobil dan pergi ngelayap . --------- Ditengah jalan dekat situ babakan ada tukang ke serabi, namanya Mpok Minah ---------Mpok Minah: “Tuan saudagar Rosyad mau kemana? Penglarisin serabi saya donk”Tuan Rosyad : “serabinya berapa duit Minah?”Mpok Minah : “ah murah, telentang seribu, tengkurap dua ribu”. Tuan Rosyad mabuk-mabukan pulang ke rumah teler … (Transkrip Hakim Siti Zulfah, Ustad Miftah, 2017)
Sahibul hikayat sebagai penutur cerita memasukkan berbagai
improvisasi dalam cerita dengan arif sesuai apa yang dipahami oleh
masyarakat, tujuannya agar cerita yang dibawakan dapat diterima
oleh pendengar sahibul hikayat malam itu, misalnya isi cerita yang
menceritakan tokoh cerita Tuan Rosyad yang kikir, ditambahkan oleh
penutur Uangnya banyak bukan dikasih ke Lebaran Betawi, tujuannya
agar pencerita dapat lebih dekat dengan konteks. Termasuk dengan
menyebut kekayaan Tuan Rosyad dengan konteks yang lebih dikenal
oleh penonton. Termasuk mengaitkan dengan unsur agama Islam
bagaimana Tuan Rosyad yang kaya raya tapi tidak menggunakan
uangnya di jalan Allah, termasuk digambarkan oleh penutur dengan
menyebut perbuatan maksiat, berfoya-foya, melupakan anak dan istri
dan akhirnya jatuh miskin dan tidak berdaya. Selanjutnya diceritakan
bahwa istri dan anak Tuan Rosyad yang dulu disia-siakan akhirnya
menjadi besar dan menjadi seorang hakim dan pada akhirnya
mengadili ayahnya yang jatuh miskin dan diadili oleh anaknya sendiri
karena mencuri. Unsur dakwah diangkat dalam sahibul hikayat yang
dibawakan, ada ganjaran bagi orang jahat dalam pesan yang umumnya
disampaikan dalam cerita sahibul hikayat termasuk cerita Hakim Siti
Zulfah.
87
Pencerita menggunakan perumpamaan-perumpamaan pada
sebuah tindakan yang menyimpang dari jalan agama, yaitu nilai agama
Islam. Hal itu diingat oleh pencerita dengan cara menambahkan di
sani-sini perumpamaan dengan cara memberi contoh penyimpangan-
nya. Pencerita sebagai tukang sahibul hikayat tidak hanya berusaha
mengingat jalan cerita Hakim Siti Zulfah, tetapi mengingat perbuatan-
perbuatan maksiat yang biasa dilakukan oleh orang kaya yang kikir
ketika sedang mengalami kejayaan. Ingatan pencerita itu tentu saja
tidak hadir begitu saja dalam mengolah cerita tapi ingatan itu sudah
hadir dalam kehidupan sehari-hari pencerita dengan kebudayaan
yang membesarkan pencerita.
Menurut Koster (2008: 39) bahwa tindakan mengingat dari
seorang pencerita, seperti sahibul hikayat Ustaz Miftah (50 tahun)
adalah cara pencerita mendapatkan bahan-bahan yang tersedia dan
yang sah untuk dituturkan, yaitu untuk menghubungkannya dengan
suara tradisi. Termasuk bagaimana agar pencerita terhindar dari
kevakuman dia bertindak sebagai sahibul hikayat dengan melakukan
ingatan pada perbuatan-perbuatan yang hitam putih agar cerita yang
dibawakan lebih hidup dalam suasana yang “geer” untuk
menghadirkan interaksi dengan penonton atau pendengar.
Pada Teks cerita Hakim Siti Zulfah tidak hanya terbatas pada
lakon atau jalan cerita Hakim Siti Zulfah, tetapi menurut Koster (2008:
40) bahwa teks dalam sahibul Hikayat melingkupi unsur-unsur seperti
bunyi suara pencerita, gerak-geriknya, atau alat media, seperti
mikrofon yang digunakan, termasuk baca-bacaan mantra atau doa
yang dibaca ketika akan memulai membawakan ceritanya. Hal yang
selalu menakjubkan dari teks lisan yang dituturkan oleh pencerita
adalah bagaimana tukang cerita atau sahibul hikayat mampu membina
teks yang dihasilkan olehnya tanpa wujud tulisan apa pun yang boleh
digunakan sebagai dasar proses penciptaan atau sutradara yang
memberi bimbingan. Untuk bisa mengerti mengapa pencerita dapat
melakukan tersebut, maka kita harus kembali pada konsep mengingat
seperti apa yang dikemukakan oleh Lord (1960) tentang bagaimana
seorang Guslar menciptakan puisi-puisi epik yang panjang, bahwa
88
cerita-cerita yang panjang dari penciptaan pencipta bukan hadir dari
hafalan tetapi merupakan hasil suatu proses yang disebut composition
in performance, yaitu penggubahan kata-kata cerita berimprovisasi
pada waktu disampaikan.
Penonton atau pendengar dapat dikatakan juga sebagai pencipta
atau pembentuk pertunjukan. Bahwa penonton tidak pasif, karena
latar belakang, penafsiran dan pewarnaan penonton akan sedikit
banyak menentukan panjang pendeknya cerita sahibul hikayat
dibawakan. Bahwa peran penonton dalam pertunjukan sahibul
hikayat harus diperhatikan keberadaannya. Sebagai pencipta cerita
yang dipertunjukkan bukan saja diciptakan oleh pencerita tetapi
penonton juga memiliki andil dalam menciptakan pertunjukan sahibul
hikayat apakah akan menarik atau tidak cerita dibawakan oleh
pencerita, maka harus diciptakan interaksi itu. Jika dilihat dari bentuk
pertunjukan tradisi lisan sahibul hikayat keunggulannya terletak pada
komunikasi yang terjadi antara pencerita, teks dan penonton harus
dilakukan. Bahwa konsep mengingat dalam sebuah pertunjukan harus
menjadi amunisi pencerita untuk tidak hanya mengingat lakon cerita
tetapi harus mengingat konteks cerita termasuk apa yang diingat oleh
penonton dan ada hubungannya dengan ingatan pada teks cerita.
Jadi revitalisasi pertunjukan sahibul hikayat tidak saja
mengupayakan adanya peran masyarakat melalui BAMUS Betawi
tetapi dalam hal ini bantuan pemerintah juga diharapkan dalam upaya
menghadirkan kembali kesenian sahibul hikayat juga dibutuhkan
peran apresiasi pencerita, penonton dan cerita untuk diolah
sedemikian rupa sehingga cerita hadir sebagai sebuah pertunjukan
yang masih dirindukan dan dipelajari bentuknya masyarakat Betawi.
Sahibul hikayat di Betawi sejak awal juga selalu membawakan
cerita-cerita dari Timur Tengah. Bagi masyarakat Betawi wilayah
tengah yang sering menyajikan pertunjukan sahibul hikayat. Budaya
Arab sebagai budaya yang dominan sudah dimulai sejak awal, hal ini
tampak dalam pergaulan identitas masyarakat Betawi tengah telah
melakukan hubungan kultural yang sangat kuat dengan kebudayaan
Arab misalnya melalui perkawinan. Penggambaran budaya Arab
89
dengan Betawi ini juga tampak dalam kehidupan masyarakat Betawi
Tengah terutama yang hidup di wilayah Tanah Abang, Pekojan dan
daerah sekitar Jakarta Pusat.
Tradisi hibriditas misalnya terlihat dalam pembawaan sahibul
hikayat Ustaz Miftah (50 tahun) layaknya seorang dai, Ustaz Miftah
membawakan cerita dengan lakon Hakim Siti Zufah dengan gaya
seorang mubalig. Pencerita menuturkan bagaimana nilai agama Islam
digunakan oleh Siti Zaenab sebagai orang tua mendidik anaknya Siti
Zulfah. Jika anak sejak dini diajarkan agama maka keselamatan akan
didapat seperti dalam contoh hidup Hakim Siti Zulfah. Namun apabila
anak sejak kecil tidak diberi pendidikan agama akan mendapat
kesengsaraan, seperti yang dialami oleh tokoh Tuan Rosyad hal ini
dapat dilihat pada pesan sahibul hikayat yang di bawakan dalam
perayaan Lebaran Betawi malam itu di Setu Babakan. Kebudayaan
yang saling mempengaruhi dalam interaksi hidup masyarakat Betawi
dan arab tampak dalam lakon sahibul hikayat. Masyarakat betawi
yang mayoritas beragama Islam tentu dapat menjadi kekuatan
identitas bagi masyarakat Betawi sebagai masyarakat kuat dalam
meyakini agama Islam.
Pertunjukan sahibul hikayat sebagai pertunjukan yang hibrid
tidak saja untuk menunjukkan bahwa pertunjukan sahibul hikayat
adalah pertunjukan yang lentur “fleksible”, hal ini juga dapat
ditunjukkan dengan kebudayaan Betawi yang egaliter, terbuka bahwa
masyarakat Betawi adalah masyarakat yang terbuka pada semua
pendatang yang masuk dan datang ke DKI Jakarta. Sahibul hikayat
dapat menjadi penanda identitas, seperti apa yang dikemukakan
Barker bahwa Identitas kultural dibentuk oleh dikursus budaya
melalui sejarah yang terkait dengan permainan kekuasaan melalui
transformasi dan pembedaan (difference).
Identitas Betawi diawali dengan terbentuknya kota Jakarta yang
bernama Batavia oleh Jan Pieterzoon, Ia merebut Jayakarta yang pada
saat itu dipimpin oleh seorang bupati yang bernama Pangeran
Jayawikarta dari Kerajaan Banten. Pasukan Belanda yang dipimpin Jan
Pieterzoon Coen berhasil merebut Jayakarta dan mengubah namanya
90
dari Jayakarta menjadi Batavia. Jayakarta dihancurkan dan diubah
menjadi Batavia. Pada saat itu hampir semua penduduknya
meninggalkan wilayah itu dan mereka mengungsi ke Banten atau ke
kaki Gunung Salak dan Gunung Gede. Setelah kejadian itu Batavia
dihuni oleh pendatang, maka kota ini pun disebut sebagai city of
migrants. Pendatang yang menghuni Batavia ketika itu terdiri atas, (1)
budak belian, (2) para pedagang Cina dan Moor, serta chetti (pedagang
Arab dan India), (3) kelompok etnik dari luar Jawa, dan (4) orang
Jawa. Berdasarkan informasi Raffles pada tahun 1815 sebagian
penduduk Batavia itu adalah budak yang berasal dari Bali dan
Sulawesi Selatan.
Berdasarkan data itu, jelas menunjukkan bahwa suku Betawi
terbentuk dari berbagai suku dan etnis Nusantara yang mayoritas
berasal dari Indonesia Timur. Di pihak lain, kebudayaan yang turut
membentuk suku baru itu, yaitu Islam dan bahasa Melayu yang
berasal dari Indonesia Barat. Jadi, dapat dimungkinkan bahwa
terbentuknya suku Betawi di Batavia saat itu melalui proses
peleburan atau melting pot. Sebagai masyarakat yang hadir dari
proses peleburan tentu muncul rasa senasib sepenanggungan dari
masyarakat yang tertekan dan dieksploitasi oleh kolonialisme dan
tuan tanah.
Penanda identitas melalui sahibul hikayat dapat terlihat dari
hubungan dengan sang pencipta, bahwa orang Betawi tidak bisa
dipisahkan dari keyakinan mereka yang kuat meyakini agama,
terutama agama Islam. Wilayah masyarakat Betawi Tengah yang
tinggal di Jakarta Pusat, seperti Tanah Abang, Pekojan dan daerah
sekitarnya yang kuat dengan penanda Islamnya. Penanda identitas ini
juga tergambar dalam cerita sahibul hikayat lakon Hakim Siti Zulfah,
bahwa pesan dari cerita yang ingin disampaikan kalau ingin selamat
dunia akhirat maka harus belajar agama sejak kecil. Hubungan dengan
sang pencipta sebagai identitas orang Betawi, hal ini sesuai dengan
filosofi hidup orang Betawi adalah “masih kecil belajar mengaji,
remaja belajar silat, (bela diri) dan sudah tua naik haji”. Keyakinan
inilah juga dapat menjadi nilai kearifan lokal masyarakat Betawi
91
bahwa bagaimana seseorang dapat mencapai kesempurnaan itu
haruslah dengan ikhtiar dan kerja keras yang tinggi agar selamat
dunia akhirat.
Penanda lainnya dalam lakon Hakim siti Zulfah juga terlihat
pada hubungan sesama manusia, misalnya saja kejujuran dalam cara
berinteraksi. Ibu Hakim Siti Zulfah mau mengakui suaminya meskipun
sudah menelantarkan dia dan ibunya beberapa tahun ketika ia sedang
mengandung anaknya. Fakta bahwa Tuan Rosyad yang kini hidup
miskin dan akan menjadi narapidana tetap diakui sebagai suami dan
diperkenalkan kepada anaknya Hakim Siti Zulfah. Orang betawi lebih
suka berterus terang, tidak ada yang disembunyikan, meski sakit
sekali pun akibatnya.
Penanda identitas lain yang berhubungan sesama manusia juga
diperlihatkan dalam cara bertoleransi. Gambaran ini terlihat dalam
cerita sahibul hikayat Hakim Siti Zulfah bagaimana kakek tua yang
menemukan Siti Zaenab sedang membutuhkan pertolongan ketika
diusir oleh suaminya dari rumah besarnya lalu ditolong dan dibantu
untuk bisa melanjutkan hidupnya bersama anaknya yang masih
dikandung. Orang Betawi yang selalu terbuka terhadap orang lain juga
tergambar dalam situasi Jakarta yang begitu terbuka menerima para
urbanisasi yang memenuhi kota Jakarta sampai mereka sendiri
tergusur ke pinggir kota Jakarta. Jika kita pantau sekarang wilayah
Jakarta Pusat yang dulu dihuni oleh orang-orang Betawi kini perlahan
tapi pasti tidak lagi menempati wilayah tanah mereka. Gambaran
inilah yang dapat menunjukkan betapa Orang Betawi adalah orang
mau bertoleransi antar sesama atau mau menjual tanahnya atas nama
pembangunan.
Penanda lain adalah masyarakat Betawi adalah masyarakat yang
egaliter, hal ini tampak benar dalam cerita sahibul hikayat bahwa
pencerita begitu dekat dengan penonton tidak ada perbedaan antara
penonton yang hadir. Semua bebas tertawa, bebas “nyeletuk”.
Termasuk yang menonton acara sahibul hikayat adalah masyarakat
yang datang dari berbagai lokasi dan tempat dari 5 wilayah di DKI
Jakarta. Ketika mereka tahu ada perayaan Lebaran Betawi mereka
92
semua tumpah dalam acara yang dapat diikuti oleh semua kalangan.
Gambaran ini juga menunjukkan bahwa orang Betawi yang egaliter
karena mereka tidak membedakan ras, suku, agama maupun
golongan. Menonton sahibul hikayat secara gratis bersama juga
menjadi simbol kebersamaan keterikatan menggambarkan suka dan
duka akan dihadapi bersama. Penanda lain yang tak kalah pentingnya
bagi masyarakat Betawi adalah sifat humoris. Orang Betawi mudah
bercanda dengan siapa pun. Hal ini juga tergambar dalam pembawaan
pencerita sahibul hikayat Ustaz Miftah, improvisasi dari lakon cerita
Hakim siti Zulfah dibuka dengan lelucon yang dibawakan dengan lucu.
Keahlian pencerita dalam sahibul hikayat adalah ketika si pencerita
mampu mengocok perut penonton yang hadir dari berbagai istilah
dan bunyi yang disampaikan dalam cerita. Misalnya dengan menyebut
perumpamaan ketika Tuan Rosyad pulang dari luar rumah
diumpamakan oleh tukang cerita bunyi pintu orang kaya “Kereeeeen
Who” sedang pintu orang miskin dengan bunyi “melaraaaat”
perumpamaan seperti itu, tentu membuat penonton geer tertawa.
Sikap humoris ini juga memang dimunculkan dalam setiap kesenian
Betawi termasuk sahibul hikayat tujuannya agar terjadi interaksi yang
baik antara pencerita dengan penonton.
B. Pertunjukan Lenong
Lenong adalah teater tradisional Betawi. Seni ini diiringi oleh
seni musik tradisional gambang kromong disertai dengan alat musik
seperti gambang, kromong, gong, drum, kempor, seruling, dan
kecrekan, serta unsur alat musik Cina seperti tehyan, kongahyang, dan
sukong. Memutar atau skenario Lenong umumnya mengandung pesan
moral, yang membantu keserakahan, lemah dibenci dan perbuatan
tercela. Bahasa yang digunakan dalam lenong adalah bahasa Melayu
(atau sekarang bahasa Indonesia) dialek Betawi.
93
Gambar 6. Pertunjukan Lenong 2013
Dok. Pribadi
Sejarah lenong berkembang sejak akhir abad 19 atau awal abad
20. Seni teater mungkin merupakan adaptasi oleh masyarakat Betawi
seni yang sama seperti “komedi bangsawan” dan “teater opera” yang
sudah ada pada saat itu. Selain itu, Firman Muntaco, seniman Betawi,
menyatakan bahwa berevolusi dari proses teater lenong musik
Gambang Kromong dan sebagai tontonan sudah dikenal sejak 1920.
Para pemain Lenong berevolusi dari lelucon-lelucon tanpa plot-
tali digantung pada sebuah pertunjukan dengan bermain sepanjang
malam dan utuh. Pada seni pertama dipamerkan dengan menyanyikan
dari desa ke desa. Acara ini diadakan di udara terbuka tanpa
panggung. Sebagai acara berlangsung, salah satu aktor atau aktris di
sekitar penonton sementara meminta sumbangan secara sukarela.
Selanjutnya, mulai Lenong dilakukan atas permintaan pelanggan
dalam acara-acara di panggung hajatan seperti resepsi pernikahan.
Baru pada awal kemerdekaan, teater rakyat ini murni menjadi spectac
panggung.
94
Gambar 7. Artis Betawi
Setelah mengalami masa sulit, dalam seni lenong yang
dimodifikasi tahun 1970-an mulai rutin dilakukan di panggung Taman
Ismail Marzuki, Jakarta. Selain menggunakan unsur teater modern
dalam tahap plot dan tata letak, Lenong yang direvitalisasi ke dalam
dua atau tiga jam dan tidak lagi sepanjang malam Selanjutnya, lenong
juga menjadi populer lewat pertunjukan di televisi, yang ditayangkan
oleh Televisi Republik Indonesia dimulai pada 1970-an. Beberapa
seniman lenong yang menjadi terkenal sejak saat itu misalnya adalah
Bokir, Nasir, Siti, dan aneh. Ada dua jenis yaitu Lenong Denes dan
Lenong preman. Dalam Lenong Denes (dari Denes dalam dialek Betawi
yang berarti, Äúdinas, Äù atau, Äúresmi, Äù), aktor dan aktris biasanya
memakai pakaian formal dan kisahnya sedang menyiapkan kerajaan
atau lingkungan kaum bangsawan, sedangkan dalam pakaian sipil
dikenakan Lenong tidak ditentukan oleh sutradara dan cerita umum
kehidupan sehari-hari. Selain itu, kedua jenis tersebut dibedakan juga
Lenong dari bahasa yang digunakan, Denes Lenong umumnya
menggunakan bahasa halus (tinggi Melayu), sementara Lenong
preman menggunakan bahasa percakapan sehari-hari. Kisah
dimainkan dalam contoh preman lenong adalah cerita tentang orang-
95
orang yang ditindas oleh tuan tanah dengan pemungutan pajak dan
munculnya tokoh pejuang doa taat yang membela rakyat dan melawan
tuan tanah jahat. Sementara itu, contoh adalah kisah Lenong Denes
1001 Cerita malam. Dalam perkembangannya, Lenong preman dan
berkembang lebih populer daripada Lenong Denes.
C. Pertunjukan Topeng Betawi
Kesenian teater masyarakat Betawi, yang pertunjukannya
hampir sama dengan lenong dan tumbuh di lingkungan masyarakat
pinggiran Kota Jakarta. Kesenian Topeng Betawi ini terdiri atas
Topeng Blantek dan Topeng Jantuk. Pertunjukkan topeng biasanya
dimaksudkan sebagai kritik sosial atau untuk menyampaikan nasehat-
nasehat tertentu kepada masyarakat lewat banyolan-banyolan yang
halus dan lucu, agar tidak dirasakan sebagai suatu ejekan atau
sindiran. Teater Topeng Betawi mulai tumbuh pada awal abad ke-20.
Karena tumbuhnya di daerah pinggiran Jakarta sehingga dipengaruhi
oleh kesenian Sunda. Saat itu masyarakat Betawi mengenal topeng
melalui pertunjukan mengamen keliling kampung.
Gambar 8. Penari Topeng, Kamis, 29 Juni 2017
Dok. Pribadi
96
Pada awalnya pementasan atau pertunjukan topeng tidak
menggunakan panggung tetapi hanya tanah biasa dengan properti
lampu minyak bercabang tiga dan gerobak kostum yang diletakkan di
tengah arena. Tahun 1970-an baru dilakukan di atas panggung dengan
properti sebuah meja dan dua buah kursi. Pertunjukkannya diiringi
dengan tabuhan seperti, rebab, kromong tiga, gendang besar, kulanter,
kempul, kecrek dan gong buyung. Lagu yang dimainkan lagu Sunda
Gunung namun khas daerah pinggir Jakarta seperti; Kang Aji, Enjat-
enjatan, Ngelantang, atau Lipet Gandes. Dahulu terdapat sebutan bagi
pecandu-pecandu Topeng Betawi yang ikut menari (ngibing) bersama
Kembang Topeng, “buaya ngibing”.
Para pemain Topeng Betawi sebagian memakai pakaian khusus
sesuai dengan peranannya dan sebagian lainnya memakai pakaian
biasa yang dipakai sehari-hari. Bagi para pemain laki-laki unsur
pakaian yang harus ada biasanya, kemeja putih, baju hitam, kaos
oblong, celana, sarung, peci atau tutup kepala, serta kedok. Sedangkan
untuk wanita unsur yang ada biasanya kain panjang atau kain batik,
kebaya, selendang, "mahkota" warna-warni yang terletak di kepala
yang biasanya disebut "kembang topeng". Selain itu, ada bagian hiasan
yang disebut ampak-ampak, andung, taka-taka, selendang (ampreng)
yaitu semacam lidah pada bagian depan pinggang yang terbuat dari
kain yang dihias, bagian ini biasanya di pakai oleh Topeng Kembang
atau Ronggeng Topeng sebagai primadona tokoh yang menonjol.
Sesuai dengan perannya, para pemain menggunakan pakaian yang
khas.
Pertunjukan topeng Betawi dengan tarian lazim disebut tari
topeng Betawi. Merupakan salah satu jenis tarian tradisional
masyarakat Betawi yang disebut juga Ronggeng Topeng. Tari Topeng
sendiri terdiri dari beberapa jenis tari, yaitu Tari Lipet Gandes
(merupakan sebuah tari yang dijalin dengan nyanyian, lawakan dan
kadang-kadang dengan sindiran-sindiran tajam menggigit tetapi lucu),
Tari Topeng Tunggal, Tari Enjot-enjotan, Tari Gregot, Tari Topeng
Cantik, Tari Topeng putri, Tari Topeng Ekspresi, Tari Kang Aji, dll.
97
Pada perkembangannya, muncul Tari Topeng kreasi baru seperti Tari
Ngarojeng, Tari Dagor Amprok, dan Tari Gitek Balen.
Alat musik pengiring yang dipergunakan dalam pertunjukan ini
adalah gendang besar, kulanter, rebab, keromong berpencon tiga,
kecrek, kempul, dan Gong Buyung. Pada pertunjukannya, didahului
dengan lagu-lagu instrumental, kemudian menyusul Tari Kedok, yaitu
Tari Ronggeng Topeng yang menggunakan tiga buah kedok secara
bergantian. Dahulu tarian ini dilakukan pada penutup acara, tetapi
sekarang dijadikan acara pertama. Pertunjukan kemudian dilanjutkan
dengan Tari Kembang Topeng yang selanjutnya dibarengi bodor
dengan diiringi lagu Aileu, Lipet Gandes, Enjot-enjotan, dan lain
sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan lakon pendek yang bersifat
banyolan. Di antara banyolan-banyolan ini terdapat cerita Bapak
Jantuk. Lakon-lakon pendek ini antara lain Benguk, Pucung, Lurah
Karsih, Mursidin dari Pondok Pinang, Samiun Buang Anak, Murtasik,
dan sebagainya. Pada perkembangan selanjutnya rombongan topeng
juga membawakan lakon panjang untuk dimainkan semalam suntuk.
Lakon panjang ini antara lain Jurjana, Dul Salam, Lurah Barni dari
Rawa Katong, Asan Usin, Lurah Murja, Rojali Anemer Kodok, Waru
Doyong Daan Dain, Kucing Item, Aki-aki Ganjen, dan sebagainya.
Sebelum memulai pertunjukan Topeng, biasanya didahului dengan
pembakaran kemenyan dan disediakan sesajen lengkap yang terdiri
dari beras, kelapa muda, berbagai minuman, rujak tujuh macam,
panggang ayam, telur ayam mentah, nasi dengan lauk-pauk, dan
cerutu atau rokok.
D. Pertunjukan Palang Pintu
Acara palang pintu bermaksud untuk menahan laju dari
rombongan pengantin pria yang hendak menuju ke kediaman
pengantin wanita untuk melamar sang wanita. Untuk bisa memasuki
ke kediaman atau daerah pengantin wanita tinggal, rombongan pria
harus bisa memenuhi persyaratan yang diajukan oleh palang pintu
dari pengantin wanita.
98
Gambar 9. Pertunjukan palang pintu, Kamis, 29 Juni 2017
Dok. Pribadi
Berawal dari iring-iringan atau biasa disebut arak-arakan besan
calon pengantin laki-laki menuju rumah calon pengantin perempuan.
Di antara rombongan besan calon mempelai laki-laki biasanya
membawa hadroh atau marawis, namun lebih sering marawis karena
lebih keras terdengar dan banyak lagu pilihan yang enak didengar.
Ada orang yang membawa seserahan atau maskawin, nah untuk yang
ini bukan remaja yang melakukan namun, biasanya Ibu-ibu. Dalam
membawakan maskawin dan lainnya yang pasti ada dalam bawaan
adalah "Roti Buaya" ini juga merupakan budaya Betawi yang ada saat
pernikahan. Lalu ada jagoan silatnya, jagoan ini yang nantinya
bertugas untuk membuka Palang Pintu yang dipersiapkan calon
pengantin wanita. Bersamaan dengan datangnya rombongan besan
pengantin pria, rombongan pihak pengantin wanita pun sudah
menunggu yang pastinya ada orang-orang yang berpenampilan seperti
jagoan, nah mereka inilah yang biasa disebut dengan Palang Pintu.
Saat rombongan pengantin pria menuju tempat mempelai wanita
untuk menikahinya, mereka harus melewati hadangan dari palang
pintu yang sudah berjaga-jaga. Ketika rombongan pengantin pria
99
sudah berhadapan dengan palang pintu, mereka harus memenuhi
persyaratan yang diajukan oleh palang pintu. Jika tidak terpenuhi
maka Mempelai pria tidak diperbolehkan masuk tempat wanita atau
daerah di mana tempat tinggalnya sebelum memenuhi persyaratan
yang diminta oleh mempelai wanita.
Adapun persyaratan tersebut diawali dengan berbalas pantun
dan adu silat antara wakil dari keluarga pria dan wakil dari keluarga
wanita. Prosesi tersebut dimaksudkan sebagai ujian bagi mempelai
pria sebelum diterima sebagai calon suami yang akan menjadi
pelindung bagi mempelai wanita sang pujaan hati. Uniknya, dalam
setiap petarungan silat, jago dari pihak mempelai wanita pasti
dikalahkan oleh jagoan mempelai pria.
Berikut penggalan pantun seperti yang kerap dilakukan dalam
prosesi Buka Palang Pintu berlangsung diwakili oleh pihak pengantin
Perempuan (P) dan pihak pengantin Laki (L):
P : Eh, Bang-bang berenti, bang budeg ape luh. Eh, bang nih ape
maksudnye nih, selonong-selonong di kampung orang. Emangnye
lu kagak tahu kalo nih kampung ade yang punye? Eh…. Bang,
rumah gedongan rumah belande, pagarnya kawat tiangnya besi,
gue kaga mao tau nih rombongan datengnye dari mane mau
kemane, tapi lewat kampung gue kudu permisi.
L : Oh…jadi lewat kampung sini kudu permisi, bang?
P : Iye, emangnye lu kate nih tegalan.
L : Maafin aye bang, kalo kedatangan aye ama rombongan kage
berkenan di ati sudare-sudare. Sebelomnye aye pengen ucapin
dulu nih Bang. Assalamu’alaikum.
P : Alaikum salam.
L : Begini bang. Makan sekuteng di Pasar Jum’at, mampir dulu di
Kramat Jati, aye dateng ama rombongan dengan segala hormat,
mohon diterime dengan senang hati.
P : Oh, jadi lu uda niat dateng kemari. Eh Bang, kalo makan buah
kenari, jangan ditelen biji-bijinye. Kalo ku udeh niat dateng
kemari. Gue pengen tahu ape hajatnye?
100
L : Oh. . jadi Abang pengen tahu ape hajatnye. Emang Abang kage
dikasih tau ame tuan rumehnye. Bang, ade siang ade malam, ade
bulan ade matahari, kalo bukan lantaran perawan yang di dalam,
kaga bakalan nih laki gue anterin ke mari.
P : Oh... jadi lantaran perawan Abang kemari?… Eh. . Bang, kage salah
Abang beli lemari, tapi sayang kage ade kuncinye, kage salah
abang datang kemari, tapi sayang tuh, perawan ude ade yang
punye.
L : Oh. . jadi tuh perawan ude ade yang punye. Eh... Bang crukcuk
kuburan cine, kuburan Islam aye nyang ngajiin, biar kate tuh
perawan udeh ade yang punye, tetep aje nih laki bakal jadiin.
P : Jadi elu kaga ngerti pengen jadiin. Eh, Bang kalo jalan lewat
Kemayoran, ati-ati jalannye licin, dari pada niat lu kage
kesampaian, lu pilih mati ape lu batalin.
L : Oh. . jadi abang bekeras nih. Eh Bang ibarat baju udah kepalang
basah, masak nasi udah jadi bubur, biar kate aye mati berkalang
tanah, setapak kage nantinye aye bakal mundur.
P : Oh. . jadi lu sangke kage mau mundur, ikan belut mati di tusuk,
dalam kuali kudu masaknye, eh. Nih palang pintu kage ijinin lu
masuk, sebelum lu penuin persaratannye.
L : Oh. . Jadi kalo mao dapet perawan sini ade saratnye, Bang?
P : Ade, jadi pelayan aje ada saratnye, apa lagi perawan.
L : Kalo begitu, sebutin saratnye. Bang.
P : Lu pengen tau ape saratnye. Kude lumping dari tangerang,
kedipin mate cari menantu, pasang kuping lu terang-terang,
adepin dulu jago gue satu-persatu.
L : Oh. . jadi kalo mao dapet perawan sini saratnye bekelai Bang.
P : Iye. Kalo lu takut, lu pulang.
L : Bintang seawan-awan, aye itungin beribu satu, berape banyak
Abang punya jagoan, aye bakal adepin satu-persatu….
Setelah adegan perkelahian, pemain palang pintu biasanya
melanjutkan dengan kembangan. Berikut adalah petikannya. Acara
Palang Pintu merupakan hasil produk umat manusia di mana dalam
101
acara tersebut adanya nilai-nilai universal. Dengan kata lain acara
Palang Pintu termasuk dalam salah satu kearifan lokal yang ada di
Indonesia. Dan kearifan lokal sendiri secara garis umum merupakan
perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang
ada. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat
setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal
merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus
dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang
terkandung di dalamnya dianggap sangat universal. Bentuk-bentuk
kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa: nilai, norma, etika,
kepercayaan, adat-istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus.
Oleh karena bentuknya yang bermacam-macam dan ia hidup dalam
aneka budaya masyarakat maka fungsinya menjadi bermacam-macam.
Dalam salah satu Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abdullah
Ibn Mas’ud disebutkan: ما راه المسلمون حسنا فهو عند اهلل حسن Artinya:
“Apa yang dipandang baik oleh umat Islam, maka di sisi Allah pun
baik”. Hadits tersebut oleh para ahli ushul fiqh dipahami (dijadikan
dasar) bahwa tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan
prinsip-prinsip syariat Islam dapat dijadikan dasar pertimbangan
dalam menetapkan hukum Islam (fiqh). Dari hadis tersebut lahir
kaidah fiqh: مة Artinya: “Suatu adat kebiasaan bisa dijadikan العادة مك
pedoman hukum”. Apabila suatu ‘urf bertentangan dengan Kitab atau
Sunah seperti kebiasaan masyarakat melakukan sebagian perbuatan
yang diharamkan semisal meminum arak atau memakan riba, maka
‘urf mereka tersebut ditolak (mardud). ‘Urf yang dimaksud di sini
adalah ‘urf khas, yaitu ‘urf yang dikenal berlaku pada suatu negara,
wilayah atau golongan masyarakat tertentu, seperti ‘urf yang
berhubungan dengan perdagangan, pertanian dan lain sebagainya.
Pentingnya posisi urf atau adat kebiasaan dalam teori hukum
Islam merupakan kesepakatan para ulama’ ushul. Posisi urf ini
menjadi penting karena dalam kenyataannya urf itulah yang menjadi
the living law (hukum yang hidup) dalam masyarakat. Membiarkan
dalil-dalil hukum Islam menjauh dari kenyataan sosial sama
102
maknanya dengan mengebiri hukum Islam itu sendiri. Karena itulah
makna teks dan konteks dipertemukan, dalil hukum dan ‘illat hukum
diteliti, serta kebiasaan yang berjalan baik diakomodasi sebagai
bagian dari hukum. Itulah makna kaidah al-’Adah muhakkamah.
Oleh karena acara Palang Pintu merupakan termasuk kearifan
lokal, maka ada banyak manfaat yang terkandung dalam acara
tersebut sebagai nilai-nilai sosiologi. Seperti disebutkan di atas, bahwa
syarat yang harus dipenuhi oleh mempelai laki-laki ada dua syarat.
Pertama dituntut punya kemampuan dalam bidang silat dengan tujuan
agar dapat melindungi calon istrinya dari orang-orang yang ingin
berbuat jahat. Dan yang kedua juga pengantin laki-laki dituntut bisa
mengaji agar nantinya bisa menjadi imam yang baik dalam segi agama
Islam dan mencontohkan hal-hal baik kepada anak dan istrinya.
Di lain pihak tradisi ini juga merupakan sebuah atraksi untuk
mempererat tali persaudaraan antara keluarga mempelai pria
maupun wanita. Selain itu juga, sebagai ujian bagi sang lelaki untuk
membuktikan kehebatannya kepada mempelai wanita bahwa dia
pantas meminang sang wanita. Oleh karenanya, wanita betawi itu
tidak boleh sembarangan menerima pria untuk menjadi pasangan
hidupnya, wanita tersebut harus jeli dalam menentukan apakah pria
tersebut pantas atau tidak, bagaimana asal-usulnya, pekerjaan, hingga
ke keluarganya.
E. Kesimpulan
Produk budaya Betawi yang berbasis industri kreatif sangat
potensial untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat di Unit Pengelola
Kawasan Perkampungan Budaya Betawi (UPK-PBB) Setu Babakan.
Namun demikian, selama ini upaya-upaya yang dilakukan belum
cukup sistematis dan berkelanjutan. Hasilnya adalah budaya Betawi
yang ada di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan belum
maksimal dikelola yang kemudian berdampak pada kearifan-kearifan
lokal tersebut, seperti pertunjukan seni budaya Betawi, kuliner
Betawi, hingga batik Betawi dalam dunia industri kreatif itu sendiri
103
masih kurang menopang ekonomi masyarakat sekitar. Oleh karena itu,
penelitian ini menjadi salah satu upaya untuk mengatasi problem-
problem tersebut.
104
KARAKTERISTIK KULINER BETAWI
A. Latar Belakang
Adapun tujuan akhir dari penelitian ini adalah mendapatkan
model karakter perkampungan budaya Betawi berupa bentuk
pengelolaan kuliner Betawi sudah dapat melakukan eksplorasi bentuk
dan rasa makanan Betawi yang berkarakter Betawi, terutama yang
baru membuka atau bergabung dengan kelompok kuliner di Setu
Babakan. Cita rasa kuliner juga telah menghasilkan suatu cipta bentuk
dan rasa yang dapat diterima oleh semua kalangan pengunjung Setu
Babakan di DKI Jakarta dan sekitarnya. Model pengelolaan yang
dilakukan harus terus menerus guna menembangkan karakter
Perkampungan Budaya Setu Babakan agar mampu bersaing dengan
cagar desa budaya yang ada di wilayah lain di Indonesia. Untuk itu
perlu kiranya dalam penelitian lanjutan perlu menuntaskan model
bahan ajar karakter Perkampungan Budaya Betawi ini dengan
melakukan diseminasi penelitian berupa adanya pengakuan para
pakar, tokoh masyarakat betawi terhadap hasil penelitian ini berupa
model dokumenter yang mampu dijangkau oleh semua pihak dalam
rangka mewujudkan Model karakteristik perkampungan Budaya
Betawi sebagai model yang mendapatkan pengakuan oleh stakeholder
dan masyarakat Betawi. Termasuk mengadakan publikasi nasional
dan internasional guna menggaungkan hasil penelitian ini sebagai
wujud memperkenalkan karakteristik Perkampungan Budaya Betawi
sebagai perkampungan budaya Betawi yang mampu bersaing dan
bermanfaat bagi masyarakat Betawi pada khususnya masyarakat Setu
Babakan dan umumnya masyarakat Betawi di DKI Jakarta maupun di
luar DKI Jakarta bahwa mereka memiliki peradaban budaya dengan
karakter dan identitas sendiri.
Karakteristik budaya Betawi berupa kuliner merupakan hasil
kreatif masyarakat yang tidak bisa dilepaskan dari pengaruh daerah
105
lain. Interaksi dengan berbagai suku dan etnik membuat
keanekaragaman kuliner Betawi semakin hari semakin bervariasi.
Namun ada yang khas dalam kuliner Betawi, misalnya kerak telor, soto
Betawi dan gado-gado Betawi hingga bir pletok.
B. Kerak Telor
Kerak telor adalah satu di antara makanan khas masyarakat
Betawi yang memiliki bentuk menyerupai martabak, tetapi isinya yang
beda. Kerak telor adalah gulungan telur yang dimasak di atas tungku
dengan cetakan wajan berisi ketan serta ubi. Isinya inilah yang
membedakan kerak telor dengan martabak telor.
Gambar 10. Foto Kuliner Bir Pletok dipamerkan dalam acara
Menyambut Tamu Asean Games 26/8/2018
Saat Anda berkunjung ke Perkampungan Budaya Setu Babakan
janganlah segan untuk jajan kerak telor dengan harga yang cukup
terjangkau. Bahkan juga di festival seperti Pekan Raya Jakarta kerak
telor tentu dengan mudah ditemukan jika ingin mencicipi kelezatan
dari makanan khas masyarakat Betawi ini.
Sebagai makanan khas, kerak telor tentu memiliki sejarah.
Makanan ini kabarnya sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda.
106
Orang Betawi, awalnya iseng mengolah campuran kelapa parut, ketan,
serta berbagai macam bumbu. Keisengan ini juga didasari dengan
banyaknya pohon kelapa di wilayah Jakarta yang saat itu namanya
masih Batavia. Melimpahnya hasil panen kelapa, membuat orang
Betawi berinovasi untuk membuat makanan lain dari kelapa tersebut.
Hasilnya, makanan ini banyak disukai. Sehingga, makanan tersebut
kemudian dijadikan jajanan di sekitar Monas.
Ciri khas dari pembuatan kerak telor sendiri ada pada
penggunaan bara api untuk memasaknya. Bagi Anda belum sempat
datang ke Jakarta atau belum pernah makan dan penasaran dengan
rasa kerak telor tersebut, Anda bisa membuatnya di rumah. Membuat
kerak telor tergolong cepat dan mudah. Anda bisa menjadikannya
sebagai teman santai di rumah untuk dinikmati bersama keluarga.
Untuk membuat kuliner kerak telor ada beberapa bahan yang
harus disiapkan, yaitu: (1) beras ketan putih 100 gram dengan
kualitas baik, (2) air 250 ml, (3) kelapa parut yang disangrai sebanyak
100 gram, (4) ebi atau udang kecil 15 gram, (5) telur bebek 5 butir, (6)
bawang goreng merah sebanyak 30 gram, (7) minyak goreng 1 sendok
makan, (8) garam, (9) gula pasir, (10) bumbu meliputi, cabai, merica,
kencur, dan jahe semua dihaluskan.
Resep kerak telor sederhana dimulai dari: (1) Rendam beras
ketan putih di dalam air selama satu malam, tiriskan, (2) Panaskan
minyak, tumis bumbu halus hingga harum., (3) Bubuhkan 1 1/2
sendok makan beras ketan putih pada wajan cekung yang sudah
panas. Siram dengan 3 sendok makan air redaman beras, biarkan
hingga agak kering, (4) Pada satu tempat, kocok 1 butir telur bebek,
1/2 sendok teh bumbu halus yang sudah ditumis, 1/2 sendok teh ebi,
1/2 sendok makan bawang merah goreng, 1/8 sendok teh gula pasir,
dan 1/8 sendok teh garam bubuk, (4) Siram campuran tersebut ke
atas ketan pada wajan, aduk sambil ratakan dan atur ketebalannya
dengan mengira-ngira. Tutup wajan hingga matang. Balik wajan
cekung di atas bara api, biarkan sampai benar-benar matang, dan (4)
Terakhir, taburi kelapa sangrai dan bawang goreng sebelum disajikan.
Kerak telor ini memang sebaiknya dimasak tidak menggunakan
107
kompor agar rasa dan aroma khasnya bisa Anda dapatkan. Namun,
untuk coba-coba di rumah, menggunakan kompor pun tidak masalah.
Hasilnya tetap enak.
Kuliner kerak telor sebagai karakteristik hasil kreasi masyarakat
Betawi yang sejak dulu ketika masa kolonial menjadi kuliner pilihan
yang telah dikenal. Kuliner ini tidak bisa dilepaskan dari ingatan
masyarakat Betawi sebagai makanan wajib di tempat dan acara
penting kebetawian seperti di Perkampungan Setu Babakan.
C. Soto Betawi
Kuliner Betawi yang satu ini adalah makanan khas yang terkenal
sebagai jenis makanan yang memiliki kuah yang segar ini ternyata
banyak sekali resepnya, dan cara pembuatannya juga berbeda-beda,
ada soto bening, soto Makassar, soto betawi, dan masih banyak soto-
soto yang tersebar luas di setiap daerah di Indonesia. Pembuatan soto
yang akan kami jelaskan adalah soto Betawi, yang merupakan soto
paling gurih dan enak bagaimana tidak perpaduan antara santan
kental dan susu sapi yang enak serta ditambah dengan potongan
daging dan jeroan sapi yang sangat gurih dan enak, menghasilkan soto
Betawi ini sebagai makanan yang sangat spesial dan enak.
Gambar 11. Soto Betawi
Dok.https://www.kompasiana.com/sotobetawi/resep-rahasia-soto-betawi-
enak-di-jakarta_54f7a64ba33311b41f8b45b0#&gid=1&pid=1
108
Soto Betawi ini merupakan makanan khas yang berasal dari
Betawi asli, yang kebanyakan memang orang asli Betawi pasti suka
dan sudah mengenalnya, dan sekarang sudah banyak juga dijual di
beberapa daerah di Jakarta, seperti di Perkampungan Setu Babakan.
Tidak banyak yang tahu bahwa makanan khas soto Betawi ini
dipopulerkan oleh Li Boen Po (ada juga yang menyebut namanya Lie
Boen Po). Dialah yang 45 tahun lalu, pertama kali menggabungkan dua
kata “soto” dan “Betawi”, yaitu untuk kuliner yang berkuah santan
dengan campuran rempah dan isi daging dan jeroan. Ia adalah
pedagang soto Betawi yang berjualan di sejak tahun 1971 di daerah
Prinsen Park atau di Wilayah Jakarta Kota.
Soto Betawi ini juga telah menjadi warisan tak benda, telah
dilakukan penilaian dan verifikasi langsung ke lapangan. Termasuk
menanyakan kepada para ahli atau pihak yang terkait dengan
keberadaan karya budaya tersebut Soto Betawi menjadi salah satu
dari 150 karya budaya yang ditetapkan sebagai Warisan Takbenda
Indonesia tahun 2016, yang perayaan dan penyerahan sertifikatnya
oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Penilaian dilakukan juga
kepada para ahli atau pihak-pihak yang terkait dengan keberadaan
karya budaya tersebut, dari segala aspek pengertian, ciri dan fungsi
serta nilai budaya yang ada dalam makanan ini.
Untuk membuat soto Betawi tidak terlalu sulit terutama dalam
menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan karena bahan-bahan soto
Betawi hampir mudah didapatkan. Bahan-bahan yang harus
disiapkan, yaitu daging sapi segar dan jeroan terpilih sebanyak 500
gram, dipotong-potong seperti dadu 1 cm. santan segar 200 ml, yang
kental dan cair, susu sapi segar/susu ultra 250 ml, air bersih
secukupnya, lengkuas dipotong 4 cm 2 cm, sereh/serai 2 batang, daun
2 lembar, mentega/minyak samin 1 sendok makan, selanjutnya ada
bumbu yang harus dihaluskan, seperti 1 sdm lada, ½ sdt ketumbar, ½
biji pala, 3 butir kemiri, 5 butir bawang putih, garam secukupnya. Cara
memasak soto Betawi adalah (1) didihkan air kemudian masukkan
daging dan jeroan bersama potongan jahe dan lengkuas. Rebus hingga
empuk. Angkat daging dan jeroan lalu tiriskan. Jadikan air rebusan
109
sebagai kaldu daging, (2) goreng daging dan jeroan dengan minyak
panas hingga berwarna sedikit kecokelatan angkat dan sisihkan, (3)
tumis bumbu-bumbu yang dihaluskan hingga wangi, masukkan santan
cair, 125 ml susu cair dan mentega biarkan hingga meletup-letup.
Angkat. (4) Masukkan tumisan bumbu beserta daun salam dan batang
serai ke dalam air kaldu daging dan jeroannya, (5) Panaskan selama
kurang lebih 10 menit. Angkat dan sajikan bersama sambal dan bahan,
(6) Sajikan bersama irisan daun bawang, tomat, kentang goreng,
teteskan jeruk limau dan kecap secukupnya, tambahkan emping
melinjo, acar dan sambal.
Kenikmatan soto Betawi ini sudah diakui oleh orang banyak,
baik orang asli Betawi maupun oleh orang luar Betawi. Hal ini
disebabkan soto Betawi bisa diterima oleh semua lidah dari mana pun.
Seperti yang diakui oleh Andi Aksan (55 tahun) dalam wawancara 28
Juli 2017 lalu di Setu Babakan bahwa soto Betawi di daerah sini sudah
menjadi langganannya jika sedang ada keramaian di Setu Babakan.
Ada beberapa penjual soto Betawi yang berderet dari Zona embrio
sampai Zona A, B, C di sepanjang Danau Setu Babakan.
D. Gado-Gado Betawi
Kuliner khas Betawi menjadi incaran para pengunjung
Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta
Selatan, pada hari kedua Pekan Lebaran Betawi 28-30 Juli 2017.
“Paling begini-begini aja. Mereka datang kebanyakan buat makan,
kumpul ramai-ramai sama keluarga atau teman, lalu pulang,” kata
Bang Amri (52 Tahun), salah satu staf pengelola di Perkampungan
Budaya Betawi Setu Babakan. Menurut dia, banyak yang bisa
dinikmati di area pelestarian warisan budaya asli Betawi tersebut.
Hampir semua kuliner khas Betawi, seperti bir pletok, dodol betawi,
soto betawi, kerak telor, ketoprak, nasi uduk, es potong, dan es
selendang mayang dijual di tempat ini.
110
Gambar 12. Kuliner Gado-Gado Tamu Asean Games 26/8/2018
Selain memburu kuliner khas Betawi, pengunjung danau buatan
seluas 30 hektare ini, terutama pengunjung cilik, ramai menyerbu
permainan yang disediakan di sana. “Sepeda air jadi favorit. Kalau pas
ramai-ramainya pengunjung, biasanya pada H+1 Lebaran, itu bisa
antre panjang sampai di sepanjang trotoar buat naik bebek-bebekan
(sepeda air berbentuk bebek),” kata Bang Amri.
Untuk resep gado-gado di Setu Babakan menurut salah seorang
penjual gado-gado, Marni katakanlah (25 tahun) bahwa di wilayah ini
resep antara gado-gado Jakarta atau Betawi dengan gado-gado
Kampung Tugu. Pertama, gado-gado resep Kampung Tugu bumbunya
menggunakan tambahan santan, kencur, dan kemiri. Santan dan
kemiri digunakan agar lebih gurih. Adapun sayuran yang digunakan
juga unik, lazimnya gado-gado menggunakan kangkung, tetapi ini
menggunakan bayam. Selain bayam, sayuran lainnya, seperti kacang
panjang, taoge, wortel, dan yang lainnya direbus. Namun, hanya sayur
kol yang dibiarkan mentah untuk menimbulkan tekstur renyah.
Berbagai sayuran itu pun diberi cuka masak agar menghasilkan rasa
asam yang meresap. Namun, bukan seperti sayur basi karena tidak
mengeluarkan bau. Gado-gado sendiri pada umumnya hanya
111
menggunakan jeruk nipis atau limau. Menurut Marni, jeruk tersebut
hanya kuat di aromanya, tetapi asamnya masih kalah dengan cuka.
“Nenek moyang kami memang suka dengan perpaduan pedas, manis,
dan asam dari cuka,” ujar Rosalia.
Untuk penyajiannya, sayuran dengan saus kacangnya tidak
diaduk menjadi satu. Saus kacang disiram di atas sayuran yang sudah
tertata, lalu diberikan potongan-potongan telur rebus, tahu, dan
kentang. Hidangan tersebut wajib disajikan saat perayaan pernikahan,
syukuran adat, dan yang lainnya bersama pindang serani.
E. Bir Pletok
Bir pletok merupakan salah satu warisan kuliner Betawi. Hingga
kini, bir pletok masih eksis di banyak perayaan Betawi salah satunya
pernikahan. Dalam momen-momen tersebut bir pletok wajib hadir di
pesta-pesta rakyat Betawi. Rasa manis, pedas, dan hangatnya yang
khas menjadikan bir ini digemari masyarakat Betawi hingga turis
asing. Perpaduan rasa khas bir pletok lahir dari 11 macam rempah
yang ada di dalamnya. Resep asli bir pletok ada 11 macam rempah,
yang pastinya ada di Betawi, atau Jakarta. Semua rempahnya punya
peranan dan menghasilkan cita rasa berbeda-beda.
Gambar 13. Foto Peneliti (Hijab Krem, Tengah) Bersama Pedagang
Kuliner Bir Pletok dalam acara Menyambut Tamu ASEAN Games
26 Agustus 2018
112
Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat bir pletok, yaitu
jahe 250 gram, kemudian cengkeh, biji pala, lada, serai, dan kapulaga
masing-masing tiga gram. Lalu kayu manis 30 gram, daun pandan
tujuh lembar, daun jeruk enam lembar, serta gula manis satu kilogram.
Semuanya untuk membuat bir pletok sebanyak enam liter, sehingga
sediakan air enam liter. Untuk warnanya sediakan kayu secang
secukupnya. Selanjutnya jahe, biji pala, lada, kapulaga, dan serai
digeprak hingga pecah atau hancur. Masukkan ke panci yang sudah
berisikan air dan dipanaskan menggunakan api sedang. Selanjutnya
masukkan rempah lainnya mulai dari daun pandan, daun jeruk,
cengkeh, dan kayu manis. Sambil diaduk, masukkan juga gula sesuai
selera manisnya. Satu rempah yang belum dimasukkan ialah kayu
secang. Kayu secang sendiri berfungsi untuk pewarnaan. Semakin
banyak semakin merah, tentu dengan kualitas secang yang bagus.
Kayu secang harus dimasukkan sendiri di akhir, dan dia sangat
bergantung sama panasnya air supaya keluar warnanya. Jadi usahakan
air sudah mendidih. Setelah mendidih, tutup panci dan diamkan
selama 20-25 menit dalam keadaan kompor menyala. Taufiq
menjelaskan ini berfungsi menyempurnakan warna dan rasa,
mengeluarkan sari-sari rempahnya ketika suhu air mendidih. Setelah
itu tiriskan dan siap dihidangkan.
Penyajian bir pletok bisa dalam keadaan hangat maupun dingin
bergantung keinginan peminatnya. Kini bir pletok sendiri sudah
bertransformasi dengan tersedianya dalam wujud sachet ataupun
bubuk di pasaran. Bir pletok yang dijual di pasaran selain ukuran botol
500 ml dengan harga Rp 20.000, juga dijual kering dalam kemasan
sachet. Adapun di Perkampungan Budaya Setu Babakan, bir pletok
disajikan dalam bentuk botol dengan beragam ukuran, serta disajikan
pula di gelas yang bisa diminum langsung oleh para pengunjung.
113
Gambar 14. Foto Kuliner Bir Pletok dalam kemasan botol dipamerkan
dalam acara Menyambut Tamu ASEAN Games 2018
F. Kesimpulan
Berbicara karakter kuliner Betawi tidak terlepas dari menu
makanan yang ada dalam masyarakat betawi, baik yang disajikan pada
saat ada acara keluarga atau acara keramaian lain yang biasa
dihidangkan oleh keluarga atau untuk menajamu tamu. Menu kuliner
Betawi memiliki karakter sesuai dengan masyarakatnya. Misal kerak
telur adalah penganan lezat yang biasa dimakan untuk melepas penat
setelah seharian bekerja. Termasuk bir pletok minuman ini selain
sebagai obat juga untuk minuman kesegaran yang tentunya memiliki
karakter yang kuat ada pada masyarakat Betawi.
114
ICON BUDAYA BETAWI
A. Ondel-Ondel
B. Bentuk/Desain
Wajah laki-laki berwarna merah, alis hitam tebal, berkumis dan
terlihat ramah
Wajah perempuan berwarna putih, bermata hitam sayu, alis
hitam melengkung, bulu mata lentik, bibir merah, telinga
bergiwang atau beranting anting dan jidatnya bermahkota.
Pakaian ondel-ondel laki-laki berwarna gelap dengan model
baju pangsi, berselempang kain bermotif batik Betawi serta
menggunakan ikat pinggang dan bawahan kain batik Betawi.
Pakaian ondel-ondel perempuan memakai busana kebaya
panjang atau baju kurung bermotif kembang-kembang dan
bawahan kain batik Betawi dengan selendang atau selempang
disangkutkan di pundak kiri ke arah pinggang kanan serta
menggunakan ikat pinggang.
115
Rambut terbuat dari ijuk warna hitam.
Hiasan kepala yang disebut kembang kelapa (manggar) dengan
jumlah 20 untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki.
C. Filosofi/Makna Ondel-Ondel
Sebagai perlambang kekuatan yang memiliki kemampuan
memelihara keamanan dan ketertiban, tegar, berani, tegas, jujur dan
anti manipulasi.
D. Fungsi, Penggunaan dan Penempatan Ondel-Ondel
Sebagai pelengkap berbagai upacara adat tradisional
masyarakat Betawi.
Sebagai dekorasi pada acara seremonial Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta, festival, pentas artis asing, pameran, pusat
perbelanjaan, Industri Pariwisata, gedung pertemuan dan area
publik yang memungkinkan dari aspek estetika dan
keselamatan umum.
Penempatan di sisi kanan kiri pintu masuk, di lobi sebagai
pelengkap foto (photo wall), di panggung pementasan atau
dalam bentuk visual di LED/Videotron, atau di tempat lain
sesuai estetika.
E. Kembang Kelapa (Manggar)
116
1. Bentuk/Desain
Bentuk kembang kelapa terbuat dari lidi yang dibungkus
dengan kertas atau plastik warna-warni.
Ukuran kembang kelapa dan tiang penyangga disesuaikan
penempatannya.
Jumlah kembang kelapa dari tiap tiang penyangga antara 60-
75 batang.
2. Filosofi/Makna
Filosofi untuk Kembang Kelapa (manggar) sebagai
perlambang kemakmuran.
Sebagai simbol dari kehidupan manusia yang bermanfaat
sebagaimana manfaat pohon kelapa.
Sebagai simbol sifat keterbukaan masyarakat dalam
pergaulan sehari-hari.
Sebagai simbol tata warna (multikultur) kebudayaan yang
hidup dan berkembang di Kota Jakarta.
3. Fungsi, Penggunaan dan Penempatan
Fungsi sebagai dekorasi statis yang memberikan nuansa
megah, meriah dan penuh keceriaan pada berbagai kegiatan,
baik di ruang terbuka maupun di ruang tertutup.
Digunakan sebagai dekorasi dinamis dan diletakkan di depan
arak-arakan dalam festival, atraksi pariwisata, pentas seni
budaya (kirab, ngarak penganten dan sebagainya).
Penempatan sebagai dekorasi statis diletakkan di samping
kanan dan kiri pintu masuk, pada kanan kiri pelaminan, pada
kanan kiri panggung, digantung di plafon dan pada titik-titik
tertentu di dalam ruangan (aula, auditorium dan lain-lain)
acara (resepsi, seminar, diskusi, dan sebagainya).
F. Ornamen Gigi Balang
1. Bentuk/Desain
Ornamen Gigi Balang berbentuk segitiga (cagak) karena
merupakan gambaran dari bentuk gunung.
Bentuk ornamen Gigi Balang:
117
Tumpal
Wajik
Wajik susun dua
Potongan Waru
Kuntum melati
2. Filosofi/Makna
Sebagai perlambang gagah, kokoh dan berwibawa.
3. Fungsi, Penggunaan dan Penempatan
Fungsi sebagai dekorasi melalui media berbentuk lampu dan
pengecatan serta media lainnya yang memungkinkan.
Penggunaan di bangunan tradisional Betawi, fasilitas publik,
gedung bertingkat, gapura, panggung pementasan, stan
pameran (booth) dan area lain yang memungkinkan dari
aspek estetika dan keselamatan umum.
Penempatan pada bagian atas (lisplang) bangunan sesuai
estetika dan keselamatan umum.
G. Baju Sadariah (Sadarie)
1. Bentuk/Desain
Baju longgar berleher tertutup (kerah Sanghai) lengan
panjang dengan dua kantong tempel di bagian depan bawah
baju.
Kopiah hitam polos sebagai penutup kepala (tinggi
disesuaikan).
118
Kain sarung plekat terlipat rapi digunakan di leher.
Celana bahan warna gelap dengan sepatu pantofel atau
celana komprang bermotif batik dengan sandal terompah.
2. Filosofi/Makna
Sebagai identitas lelaki rendah hati, sopan, dinamis dan
berwibawa.
3. Fungsi dan Penggunaan
Fungsi dan penggunaan sebagai seragam karyawan berbagai
kantor pemerintah dan swasta, industri pariwisata, sekolah dan
berbagai acara seremonial, obyek dan atraksi pariwisata serta
pentas seni budaya.
H. Kebaya Kerancang
1. Bentuk/Desain
Bahan kebaya dibordir kerancang dengan motif kembang
pada bagian bawah kebaya dan pada pergelangan tangan.
Hiasan rambut dapat menggunakan sanggul dengan model
Konde Bundar atau model lain yang disesuaikan dengan
pemakainya.
119
Menggunakan kain sarung batik Betawi dengan kepala kain
bermotif tumpal, tombak, buket dan sebagainya.
Alas kaki selop tutup.
Perhiasan yang dikenakan, antara lain: peniti rante susun
tiga, anting air seketel atau giwang asur, gelang listering atau
gelang ular, cincin bermata dan kalung tebar. Keserasian
menjadi unsur penting bagi pemakaiannya.
2. Filosofi/Makna
Sebagai perlambang keindahan, kecantikan, kedewasaan,
keceriaan dan pergaulan yang mengikuti kearifan, aturan dan
tuntunan leluhur. Tujuannya untuk memelihara keanggunan
dan kehormatan perempuan.
3. Fungsi dan Penggunaan
Fungsi dan penggunaan sebagai seragam karyawati berbagai
kantor pemerintah dan swasta, industri pariwisata, sekolah dan
berbagai acara seremonial, obyek dan atraksi pariwisata serta
pentas seni budaya.
I. Batik Betawi
Pengelolaan batik Betawi adalah melakukan pemeliharaan dan
pemasaran terhadap batik Betawi yang dapat mendatangkan sumber
penghasilan bagi kelompok masyarakat pemilik tradisi. Pada zaman
dulu, konon tempat usaha pembuatan batik berkembang sangat pesat
dan subur di tanah Betawi seperti di daerah kawasan; Karet Tengsin,
Palmerah, Kebon Kacang, dan Bendungan Hillir yang merupakan
daerah-daerah produksi batik yang populer dan terkenal. Proses
pembuatan batik pada dulunya dilakukan di rumah-rumah penduduk.
Karena industri batik yang berkembang pesat, maka pada waktu itu di
daerah Jakarta pernah didirikan Koperasi Batik.
Namun sayangnya, setelah masa perjalanan cukup lama,
produksi kain batik Betawi kian hari semakin menyurut. Hal ini
disebabkan oleh pengembangkan tata kota Jakarta pada saat itu yang
membuat semakin tingginya nilai harga tanah di Jakarta. Dan
membuat daerah produksi batik ini tergusur oleh gedung-gedung
120
perkantoran serta pusat perbelanjaan, sehingga membuat para pelaku
produsen batik Betawi rumahan harus memindahkan proses
produksinya ke daerah Tangerang.
Gambar 15. Foto Motif Batik Betawi di UPK-PBB Setu Babakan
1. Bentuk dan Bahan
Batik Betawi berbentuk kain panjang dan kain sarung yang
motifnya dikerjakan dengan tulis dan cap. Bahan kainnya
berupa sutera, ATBM, prima, primis dan dobi.
Motif batik Betawi antara lain : Dododio, Mak Ronda,
Rasamala, Nusa Kelapa, Lereng, Ondel-Ondel, Pesalo,
Salakanagara, Albetawi, Kodangdia, Langgara, Warakas, flora
fauna asli Betawi, Daun Tarum, Nderep, Kampung Marunda,
Ngeluku (Bajak Sawah), Ngelancong/Bedemenan, Nandur,
Burung Hong, Numbuk Padi, Baritan, Sulur Jawara, Ronggeng
Uribang, Galur Ondel-Ondel, Kuntul Blekok, Payung Cokek,
Ulung-Ulung, Bondol Biru dan lain-lain.
121
2. Filosofi/Makna
Sebagai keseimbangan alam semesta untuk memenuhi hidup
yang sejahtera dan berkah.
3. Fungsi dan Penggunaan
Fungsi dan penggunaan sebagai seragam karyawan/karyawati
berbagai kantor pemerintah dan swasta, industri pariwisata,
sekolah, dan berbagai acara seremonial, obyek dan atraksi
pariwisata serta pentas seni budaya.
4. Pengolahan Batik Betawi
Pengelolaan batik Betawi pada komunitas Batik Setu
Babakan yang dilaporkan oleh Syaiful Amri (53 Tahun)
pengurus yayasan keluarga batik Betawi Setu Babakan dengan
bantuan laporan dari K.H. Wahiuddin Sakam, H. Tatang Hudayat
S.H., Sumiati Adi Susilo, Pengurus, Ketua: Yahya Andi Saputra,
Sekretaris: Rudi Haryanto bahwa pengelolaan batik Betawi di
Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi (UPK-
PBB) Setu Babakan terlihat sudah mulai berjalan. Pihak
pengelola menggandeng para pengrajin batik Betawi agar
mereka dapat berpartisipasi dan berperan aktif menghidupkan
batik Betawi di UPK-PBB Setu Babakan. Hal tersebut
berdasarkan wawancara peneliti dengan pengelola UPK-PBB
Setu Babakan, Bapak Syaiful Amri pada 06 Juni 2018. Adapun
transkrip wawancaranya adalah sebagai berikut.
Batik atau seni batik, di Betawi telah berkembang sejak
abad 19. Sejak itu hingga masuk abad ke-20, semua batik yang
dihasilkan ialah batik tulis. Sementara batik cap –orang Betawi
menyebutnya batik ceplok– dikenal setelah perang dunia I
sekitar tahun 1920. Batik Betawi berkembang sejak abad ke 19.
Motifnya mengikuti gaya batik pesisiran (Gresik, Surabaya,
Madura, Banyumas, Pekalongan, Tegal, dan Cirebon). Daerah
pembatikan yang dikenal di Jakarta tersebar di dekat Tanah
Abang yaitu: Karet Tengsin, Karet Semanggi, Bendungan Ilir,
Bendungan Udik, Sukabumi Ilir, Pelmerah, Petunduan,
Kebayoran Lama, dan daerah Mampang Prapatan serta Tebet.
122
Salah satu nama motif batik Betawi yang cukup masyhur adalah
Bambu Kuning, Sèsèr Gerimis, Elèr Kembang-Kembang, Iket
Buketan, dan lain-lain. Sayang memang, generasi terakhir
pembatik batik itu, batik Bambu Kuning misalnya, meninggal
tahun 1990-an. Semula motif yang dipakai adalah motif flora
khas pesisir. Pewarnaan pun secara alamiah. Batik Betawi tidak
digunakan oleh kelas sosial tertentu.
Fungsi batik terutama di komunitas dan masyarakat Betawi
utamanya orang Setu Babakan sangat penting. Batik dipakai
sebagai pakaian harian maupun khusus. Yang khusus tentu
bahannya kualitas bagus. Di masyarakat Betawi, batik tentu
memiliki fungsi sesuai status sosial pemakainya. Meski motifnya
sama, tapi kualitas bahannya berbeda. Umumnya motif tumpal
menjadi kekhasan batik Betawi. Motif ini melambangkan
keseimbangan hidup. Masyarakat Betawi, khususnya yang
tinggal di Setu Babakan memanfaatkan batik untuk tujuannya
yang sama, keindahan dan kesopanan berpakaian. Lebih lanjut
bahwa nilai pada motif batik Betawi secara universal sama saja.
Nilai memelihara lingkungan, nilai silaturahmi, nilai gotong
royong, nilai keteguhan, nilai kebenaran, nilai identitas, dan
sebagainya. Saat ini tercatat sudah lebih dari 100 corak batik
Betawi dan tentu sesuai dengan pakem dan sesuai dengan
karakter hidup orang Betawi. Misalnya kebersamaan,
keterbukaan, agamis, cinta lingkungan, dan sebagainya.
Melihat potensi yang besar batik Betawi, maka produk
budaya ini wajib menjadi perhatian serius dengan program-
program yang sistematis dan berkelanjutan. Program batik
Betawi di setu babakan bertujuan pemberdayaan masyarakat.
Jika kesadaran masyarakat sudah kuat dan baik dengan proses
ini, tentu akan melahirkan UKM-UKM mandiri. Sampai saat ini
kami masih membina masyarakat agar memiliki ketetapan hati
bergiat di per batikan. Namun sayangnya, binaan dari dinas
UKM belum ada. Para pegiat batik Betawi saat ini berbuat dari
mereka dan untuk mereka. Tentu mereka ingin mengelola
123
secara modern. Salah satu langkah yang mereka lakukan adalah
dengan membuat struktur organisasi, sudah legal secara hukum,
artinya sudah berakta notaris, sudah terdaftar di
Kemenkumham, dan sudah melengkapinya dengan ketentuan
administratif lainnya.
Pemasarannya ditempuh dengan berbagi cara, baik cara
modern seperti online dan media sosial; juga dengan cara
tradisional, seperti getok tular. Tapi umumnya masih terkendala
dengan ketiadaan galeri dan tempat pamer atau kios. Selain itu,
masalah pemasaran yang peneliti temukan adalah belum
tersedianya informasi melalui website yang secara khusus
menginformasikan produk batik Betawi di Perkampungan
Budaya Betawi Setu Babakan. Galeri yang representatif dan
ketersediaan media website dapat menjawab keingintahuan
masyarakat tentang batik Betawi dan untuk menjawab
permintaan pasar cukup tinggi dan tentu disesuaikan dengan
pasar kelas menengah bawah.
Proses pengelolaan batik Betawi di rumah Yayasan Batik
Setu Babakan hampir sama dengan batik lainnya. Dimulai dari
menggambar motif pada kertas yang kemudian dijiplak ke kain
untuk batik tulis, atau dicetak motifnya pada tembaga untuk
batik cap. Bicara soal batik Betawi, tepat rasanya untuk
langsung belajar dari Keluarga Batik Betawi (KBB) yang
berlokasi di Kampung Budaya Betawi, Setu Babakan, Jakarta
Selatan. Ditemui di sela-sela kerja, Ade selaku pemimpin KBB
menceritakan proses, ragam motif, hingga pemasaran Batik
Betawi. Hampir sama dengan batik lainnya, batik Betawi juga
memiliki batik tulis dan batik cap. Proses pembuatan keduanya
hanya berbeda di pengerjaan setelah motif selesai digambar.
Untuk batik tulis sendiri, nantinya motif akan dijiplak ke kain
sepanjang 2 hingga 2,5 meter. Sedangkan untuk batik cap, motif
akan dibuat dari bahan tembaga.
124
Gambar 16. Foto Pengelolaan proses menggambar corak Batik Betawi
pada 29/05/18 di Rumah Yayasan Batik Setu Babakan
Motif Batik Betawi sendiri memiliki keunikan karena
banyak terinspirasi dari lingkungan Jakarta dan kekayaan
budaya Betawi. Seperti Pantai Ancol, ondel-ondel hingga
makanan khas Kembang Goyang dan Akar Kelapa. Ade (34
tahun) menjelaskan, motif Batik Betawi lebih dinamis dan
modern dibandingkan motif batik dari kebudayaan lain. Selain
itu, banyak motif yang tidak memiliki arti filosofis tertentu.
“Paling ondel-ondel yang dianggap bisa mencegah hal negatif,
atau warna cerah sesuai dengan orang Betawi yang ceria,”
tambahnya. Ade juga menyebut bahwa ondel-ondel menjadi
motif yang paling digemari pembeli. Untuk pembuatan motif,
batik tulis dan batik cap memiliki perbedaan ukuran. Motif batik
tulis dapat berukuran 60 cm hingga 70 cm. Sedangkan untuk
motif batik cap, hanya berukuran 18 cm x 18 cm. Oleh karena
itu, pemindahan motif untuk batik tulis dapat memakan waktu
hingga 3 bulan, dibandingkan batik cap yang hanya butuh
sekitar 3 hari. Setelah motif dipindahkan ke kain, proses
selanjutnya yakni pewarnaan.
125
Di Perkampungan Budaya Betawi, Ade mengaku hanya
memakai pewarna alami yang didapat dari secang untuk warna
merah, tingi untuk warna merah pekat, tegeran untuk warna
kuning cerah, jelaweh untuk warna kuning pekat, dan indigo
untuk warna biru. Untuk bagian kain yang ingin dipertahankan
warna merahnya, pengrajin batik menutup bagian tersebut
dengan lilin. Setelah tertutup, bagian yang terbuka dapat
diwarnai kembali. Kemudian, kain siap untuk proses pelepasan
lilin dengan cara direbus.
Gambar 17. Foto Pengelolaan proses membatik Batik Betawi
29/05/18 di Rumah Yayasan Batik Setu Babakan
Gambar 18. Foto Pengelolaan proses membatik Batik Betawi
29/05/18 di Rumah Yayasan Batik Setu Babakan
126
Gambar di atas perajin menyelesaikan pembuatan batik
khas Betawi di rumah produksi Keluarga Batik Betawi, kawasan
budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan. Kain batik usaha
rumahan dengan motif khas Betawi seperti ondel-ondel, bunga
manggar dan Monumen Nasional (Monas) tersebut dijual
dengan harga mulai dari Rp 120.000 hingga Rp 350.000 per
helai. Usaha ini juga untuk melestarikan keberlangsungan
perajin batik tradisional yang keberadaannya mulai sulit
ditemukan akibat banyaknya usaha sejenis dengan pola
produksi lebih modern.
Gambar 19. Foto Pendataan jumlah batik Betawi di Produksi
29/05/18 di Rumah Yayasan Batik Setu Babakan
Gambar 20. Foto Pengelompokan jumlah dan jenis batik Betawi
di Produksi 29/05/18 di Rumah Yayasan Batik Setu Babakan
127
Kain-kain batik yang sudah jadi, siap untuk dipasarkan. Di
KBB sendiri, batik cap dihargai Rp 135 ribu hingga Rp 230 ribu.
Sedangkan untuk batik tulis, dapat mencapai Rp 10 juta,
tergantung kepadatan motif dan waktu pengerjaan.
Gambar 21. Foto Peneliti (Hijab krem, kanan) mengunjungi sebuah
stan Industri Kreatif Batik Betawi yang di pamerkan dalam acara
Pertunjukan 26/08/18 di PBB Setu Babakan
Adapun tujuan akhir dari penelitian ini adalah mendapatkan
model karakter perkampungan budaya Betawi berupa bentuk
pengelolaan pertunjukan yang mampu berkolaborasi dengan bintang
komunitas tradisi yang telah memiliki jam terbang, tujuannya saling
memberi pengalaman dan pengetahuan, termasuk penurunan atau
pewarisan pertunjukan yang berkarakter dengan cara bertukar ilmu
dalam pertunjukan antara pemain muda dengan senior. Selanjutnya
untuk pengelolaan kuliner sudah dapat melakukan eksplorasi bentuk
dan rasa makanan Betawi yang berkarakter Betawi, terutama yang
baru membuka atau bergabung dengan kelompok kuliner di Setu
Babakan. Cita rasa kuliner juga telah menghasilkan suatu cipta bentuk
dan rasa yang dapat diterima oleh semua kalangan pengunjung Setu
Babakan di DKI Jakarta dan sekitarnya. Sementara untuk pengelolaan
batik Betawi sudah mengusahakan batik yang dikelola secara modern.
128
Pencapaian ini diharapkan tidak cepat puas dengan pencapaian yang
ada. Model pengelolaan yang dilakukan harus terus menerus guna
menembangkan karakter Perkampungan Budaya Setu Babakan agar
mampu bersaing dengan cagar desa budaya yang ada di wilayah lain di
Indonesia. Untuk itu perlu kiranya dalam penelitian lanjutan perlu
menuntaskan model bahan ajar karakter Perkampungan Budaya
Betawi ini dengan melakukan diseminasi penelitian berupa adanya
pengakuan para pakar, tokoh masyarakat betawi terhadap hasil
penelitian ini berupa model dokumenter yang mampu dijangkau oleh
semua pihak dalam rangka mewujudkan Model karakteristik
perkampungan Budaya Betawi sebagai model yang mendapatkan
pengakuan oleh stakeholder dan masyarakat Betawi. Termasuk
mengadakan publikasi nasional dan internasional guna
menggaungkan hasil penelitian ini sebagai wujud memperkenalkan
karakteristik Perkampungan Budaya Betawi sebagai perkampungan
budaya Betawi yang mampu bersaing dan bermanfaat bagi
masyarakat Betawi pada khususnya masyarakat Setu Babakan dan
umumnya masyarakat Betawi di DKI Jakarta maupun di luar DKI
Jakarta bahwa mereka memiliki peradaban budaya dengan karakter
dan identitas sendiri.
J. Kerak Telor
1. Bentuk dan Bahan
Beras ketan putih
Garam
Merica bubuk
Kelapa muda parut yang disangrai (serundeng)
Telur ayam/telur bebek
Ebi
Bawang goreng
2. Filosofi/Makna
Sebagai sisi kehidupan manusia yang mengalami perubahan
lingkungan secara alamiah. Kerak Telor sebagai perlambang
pergaulan yang harmonis.
129
3. Fungsi dan Penggunaan
Sebagai menu makanan ringan atau selingan (kudapan). Sebagai
salah satu menu pada industri pariwisata, acara seremonial
jamuan makan, stan di acara pameran, atraksi pariwisata dan
pentas seni budaya.
K. Bir Pletok
1. Bentuk dan Bahan
Bir Pletok adalah minuman berwarna merah yang menyehatkan
dan menyegarkan, dapat dihidangkan dingin atau agak panas.
Bahan utama:
Air, gula pasir, kayu manis, jahe, serai, cengkeh, kayu (babakan)
secang, buah pala, bunga pala, lada bulat di belah, kapulaga,
cabai Jawa, daun jeruk purut, daun pandan, gardamom seed
(gardamunggu) dibelah dan garam.
2. Filosofi/Makna
Bir Pletok dimaknai sebagai penopang hidup sehat secara lahir
dan batin dan juga sebagai upaya mengapresiasi serta mengisi
hidup yang tidak boleh kendor sampai pada titik yang paling
utama yakni matang.
3. Fungsi dan Penggunaan
Sebagai minuman yang menyehatkan dan menyegarkan. Sebagai
salah satu menu pada industri pariwisata, acara seremonial
jamuan makan, stan di acara pameran, atraksi pariwisata dan
pentas seni budaya.
L. Kesimpulan
Ikon Betawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
dimaksudkan sebagai upaya pelestarian melalui pengenalan yang
menggambarkan ciri khas masyarakat Betawi dan jati diri Provinsi
DKI Jakarta sebagai daya tarik wisata. Hal ini tergambar pasal 3
Penetapan Ikon Budaya Betawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) bertujuan: a. meningkatkan rasa ikut memiliki dan
menanamkan kebanggaan terhadap budaya Betawi secara aktif dalam
130
kehidupan sehari-hari masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah; dan
b. sebagai sarana promosi kepariwisataan dan mendorong
perkembangan industri kreatif berbasis budaya.
131
DAFTAR PUSTAKA
Attas, Siti Gomo, 2016. “Konservasi Sastra Dan Bahasa Lisan Di
Wilayah Pesisir Jakarta Utara” Hibah Penelitian P2M, Fakultas
Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta.
----------, 2015. Proses Penciptaan Gambang Rancag: Analisis Fungsi dan
Konteks Pertunjukan, Disertasi, Program Pasca Sarjana Pend.
Bahasa Indonesia UPI.
----------, 2014 “Pemertahanan Nilai Kearifan Lokal Betawi dalam
Tradisi Gambang Rancag Melalui Pewarisan”, Prosding pada
Forum Ilmiah X, Seminar Internasional Bahasa, Sastra. Seni
dan Pembelajarannya (Thenth Scientific Forum International
Seminar Workshop on Languages, Literature, Arts, and Learning
2014), pada Rabu-Kamis, 19-20 November 2014 di Auditorium
FPMIPA UPI dan Gedung FPBS UPI Bandung.
----------, 2013 “Mengusung Pembelajaran Sastra Lisan Gambang
Rancag Menuju Pembelajaran Inovatif Lokabahasa: Jurnal
Kajian Bahasa, Sastra, dan Budaya Daerah serta Pengajarannya
Lokabahasa. Vol. 5 Nomor 5.Hlm.171-183, Bandung Oktober
2013 ISSN 2338-6193.
----------, 2013. “Restorasi Kultural Cerita Rancag si Pitung melalui
Pertunjukan Gambang Rancag Kelompok Gali Putra Pekayon di
Masyarakat Betawi”, Prosiding pada Kongres Internasional
Foklor Asia III (The 3 Internasional Congres on Asia Foklore
2013) padaJumat-Minggu, 7-9 Juni 2013 di Kraton Yogyakarta
dan Hotel Inna Garuda Yogyakarta.
----------. 2013. “Mengusung Cerita Topeng Betawi Tempo Doeloe
Menuju Pertunjukan Dunia”. Literasi Jurnal Ilmu-Ilmu
Humaniora Literasi Volume: 3 No.1 Hlm. 52-61, Jamber Juni
2013. ISSN 2088-3307
Bandari. 2010. Kamus Betawi Indonesia dan Indonesia. Betawi:
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
132
Budiaman, dkk. 1997. Foklor Betawi. Jakarta: Pustaka Jaya.
Budianta, Melani. 2008. “Sastra Indonesia Modern Kritik Poskolonial”:
Representasi Kaum Pinggiran dan Kapitalisme, Indonesia:
Yayasan Obor Indonesia.
Castles, Lance. 2007. Profil Etnik. Jakarta, terjemahan Gatot Triwira,
Depok: Masuji Jakarta.
----------. 1967. The Ethnic Profil of Djakarta Indonesia, Penerjemah
Gatot Petriwira. Jakarta: Masup Jakarta.
Chaer dan Leoni Agustina. 2010. Sosiolinguistik Perkenalan Awal.
Jakarta: IKAPI.
Chaer. Abdul, 2009a. Kamus Dialek Jakarta, edisi revisi. Depok: Masup
Jakarta.
Chaer. Abdul. 2018. Pantun Zainudin al Batani. Dalam Peluncuran
Buku 1000 Pantun di Setu Babakan 2018.
----------. 2012. Folklor Betawi: Kebudayaan Kehidupan Orang Betawi.
Jakarta: Masup Jakarta.
----------. 2005. “Perkembangan Bahasa Melayu dan Jakarta”. Jurnal
Betawi. Tahun 1 Nomor 1
Chamber-Loir, Hendri. 2009. Hikayat Nakhoda Asyik, Syafirin Bin
Usman dan Hikayat Merpati Mas, Muhammad Bakir. Jakarta:
Masup, Ecole Francaise d’Extreme-Orient, Perpustakaan
Nasional Republic Indonesia.
DKI Jakarta. "Wilayah Budaya Betawi." Portal Resmi Pemerintah DKI
Jakarta. Jakarta.go.id, Jan. 2010. Web. 12 Mar 2017.
<https://jakarta.go.id/v2/news/2010/01/wilayah-budaya-
netawi#.WMVNiqCyTqA>>
Erwantoro, Heru. 2014. Etnis Betawi: Kajian Historis. Dalam Jurnal
Patajala Vol. 6 No. 1, Maret. 3014:1-16. From: https://
www.researchgate.net/publication/323785406_ETNIS_BETA
WI_KAJIAN_HISTORIS [accessed Sep 10 2018].
Ghozally, Fitri, R. 2004. Dari Betawi Menuju Jakarta. Jakarta: Mal Corp.
Grijns, CD. 1991. Kajian Bahasa Melayu Betawi. Jakarta: PT Pustaka
Utama Grafiti.
133
H.M., Zainuddin. 2012. 21 Asal-Usul Djakarta Tempo Doeloe: Disertai
Teka-teki, Foto, dan Kesaksian Unik yang Membawa Anda ke
Masa Lalu. Jakarta: Ufuk Press.
Hendrowinoto, Nurwanto dkk.1998. Seni Budaya Betawi Menggereng
Zaman. Jakarta: denah kebudayaan Betawi.
Ikranagara, Kay. 1988. Tata Bahasa Melayu Betawi. Jakarta: Balai
Pustaka.
Kiftiawati. 9 Maret 2011. “Bertahan dalam Teriknya Zaman Nyi Meh,
Kembang
Kleden-Probonegoro, Ninuk. 2015. “Pengalihan Wacana: Lisan ke
Tulisan dan Teks” Metodologi Kajian Tradisi Lisan, Jakarta:
Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
----------. Teater Lenong Betawi. Jakarta: Balai Pustaka.
Kunst, Japp. (1934). Music in Java: Its history, its theory, its tecnique.
The Hague: Martinus Nij hoff.
Madjoindo, Aman Dt.2002. Si doel anak Jakarta. Jakarta: Balai Pustaka.
Marnita, Rita. 2011. “Pergeseran Bahasa dan Identitas”. Jurnal
Masyarakat Indonesia, Vol XXXVII/No.1, hal: 137-1160. Jakarta:
LIPI Press.
Muhadjir, 2018. Peran Bahasa Betawi tulis di Jakarta: Disampaikan
dalam Seminar Sejarah Pelacakan Peradaban Jakarta 2018.
----------. 2005. “Peran Bahasa Melayu Jakarta di Antara Bahasa-Bahasa
Melayu Lain di Indonesia”. Prosiding Seminar Betawi dan
Jakarta: Tinjauan Budaya. Depok: Pusat Penelitian dan
kemasyarakatan dan Budaya Direktorat Riset dan Pengabdian
Masyarakat Universitas Indonesia.
----------. 2002. Sastra Tulis Melayu Klasik Betawi. Bunga Rampai Sastra
Betawi. Jakarta: Dinas Kebudayaan dan Permusiuman Provinsi
DKI Jakarta.
----------, 2000. Bahasa Betawi Sejarah dan Perkembangannya. Jakarta;
Puslitbang Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB-UPI)
dengan The Ford Foundation dalam Rangka Program
Pemetaan Bahasa Nusantara.
----------. 1999. Bahasa Betawi: Sejarah dan Perkembangannya. Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia.
134
Perpusnas RI, 2013. Katalog Naskah Sosial Budaya Pecenongan Koleksi
Perpustakaan Nasional: Sastra Betawi Akhir Abad ke -19.
Jakarta: Perpusnas RI.
Ruchiat, dkk. 2003. Ikhtisar Kesenian Betawi. Jakarta: Dinas
Kebudayaan dan Permusiuman Provinsi DKI Jakarta.
Salmon, Galudine, 1981. Literature in Malay by Chinese of Indonesia; A
Procisional Annotated Bibliography. Paris: Etude Insulindiene-
Archipel.
Shahab, Yasmin Zaki. 2001. Rekacipta Tradisi Betawi: Sisi Otoritas
dalam Proses Nasionalisasi Tradisi Lokal. Jurnal Antropologi
Indonesia Nomor 66. Depok: Universitas Indonesia, (Hlm. 47-
56).
Suwito. 1982. Pengantar Awal Sosiolinguistik: Teori dan Problema.
Surakarta: Henary Offset Surakarta
Yowono, Prapto, et al. 2010. “Peran dan Fungsi Kampung Setu
Babakan dalam Upaya Pelestarian dan Pengembangan
Kesenian Betawi”, dalam Prosiding Seminar Nasional Hasil
Pengkajian Budaya Betawi 14-15 Desember 2010. Depok:
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI.
Sumber Lain
Indrasafitri, Dina. 2012. Betawi: Beetween Traditional and Modernity,
The Jakarta Post dalam http://www.thejakartapost.com/news/
2012/04/26/betawi-between-tradition-and-modernity.html
Knorr, Jacqueline (2014). Creole Identity in Postcolonial
Indonesia.Volume 9 of Integration and Conflict Studies.
Berghahn Books.hlm. 91. ISBN 9781782382690
The Jakarta Post, 2011. Debunking the ‘native Jakartan Myth’ dalam
http://www.thejakartapost.com/news/2011/11/07/debunki
ng-native-jakartan-myth.html
http://langgambudaya.ui.ac.id/betawi/video/detail/9/profil-
kesenian-tanjidor/