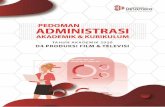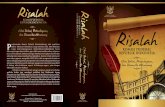Dinamika Perkembangan Ilmu Pengetahuan dalam Islam
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Dinamika Perkembangan Ilmu Pengetahuan dalam Islam
1
DINAMIKA PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DALAM ISLAM
Oleh: Djamaluddin Perawironegoro
A. Pendahuluan
1. Latarbelakang
Tiga di antara temuan ilmiah terpenting di Dunia Islam yang sangat
berpotensi memengaruhi perjalanan kehidupan umat Islam secara mendalam dan
menyeluruh dalam memasuki abad ke -15 H, selanjutnya memasuki abad ke-21
M, adalah; (1) Problem terpenting yang dihadapi umat Islam saat ini adalah
masalah ilmu pengetahuan; (2) ilmu pengetahuan modern tidak bebas nilai (netral)
sebab dipengaruhi oleh pandangan-pandangan keagamaan, kebudayaan, dan
filsafat, yang mencerminkan kesadaran dan pengalaman manusia Barat; (3) umat
Islam, oleh karena itu, perlu mengislamkan ilmu pengetahuan masa kini dengan
mengislamkan symbol-simbol linguistik mengenai realitas dan kebenaran.
Demikian diungkapkan oleh Syed M. Naquib Al-Attas dikutip oleh Wan Mohd
Nor Wan Daud dalam The Educational Philosophy and Practice.1
Ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan berbasis nilai, dan Islamisasi ilmu
adalah hal yang memberikan perubahan pada kondisi umat Islam di masa yang
akan datang. Hal ini bukan sesuatu yang mustahil, mengingat dalam sejarahnya,
umat Islam pernah menjadi “leader” dalam pengembangan ilmu pengetahuan di
masa kejayaannya.
Islamisasi ilmu adalah perkembangan terakhir dari perkembangan ilmu
pengetahuan dalam Islam. Senada dengan hal tersebut diungkapkan oleh Ismail
Raji Al-Faruqi dengan Islamization of knowledge. Dalam konteks lain Imam
Suprayogo menggunakan istilah Integrasi ilmu, Amin Abdullah menyebutnya
dengan integrasi-interkoneksi, dan Haidar Bagir menyebutnya dengan reintegrasi.
Fenomena ini bukan hanya sekedar teori dan tanpa realisasi. Ide ini
dilanjutkan dengan serius oleh para pakar tersebut. Lihatlah dengan usaha Syed
1 Wan Mohd Nor Wan Daud, The Educational Philosophy and Practice of Syed M. Naquib Al-
Attas, alih bahasa Hamid Fahmi, dkk. (Bandung: Mizan, 1998), hal.317
2
M. Naquib Al-Attas dengan mendirikan ISTAC (International Institute of Islamic
Thought and Civilization) di Malaysia sejak tahun 1987. Al-Attas juga
membangun budaya organisasi lembaga dengan merancang dan mendesain
bangunan kampus ISTAC, termasuk auditorium dan masjid dengan lanskap dan
dekorasi interior yang bercirikan seni arsitektur Islam yang dikemas dalam
sentuhan tradisional dan gaya cosmopolitan.
Imam Suprayogo menggagas Integrasi ilmu yang diwujudkan dalam
symbol Pohon Ilmu UIN Malang. Dimana Bahasa Arab dan Inggris, Pancasila,
Filsafat, Ilmu Alamiah Dasar, dan Ilmu Sosial Dasar sebagai “akar”. Al-Qur‟an
dan Sunnah, Sirah Nabawiyah, Pemikiran Islam, dan Masyarakat Islam sebagai
batang pohon. Dan Psikologi, Fisika, Kimia, Informatika, Arsitektur, Matematika,
Biologi, Humaniora, Budaya, Tarbiyah, Al-Akhwal Al-Syakhsiyah. Symbol
tersebut tidak sekedar symbol, namun menjadi kurikulum dalam pengembangan
UIN Malang. Sebagai contoh, wujud integrasi ilmu seorang cendekia harus
memiliki kunci yang digunakan untuk membuka khazanah ilmu pengetahuan
tersebut, dan kunci tersebut adalah bahasa, maka penguasaan bahasa mutlak
dibutuhkan. Sehingga untuk menunjang penguasaan bahasa, setiap mahasiswa
diwajibkan untuk mengikuti program bahasa selama setahun di asrama.
Amin Abdullah dengan integrasi-interkoneksi UIN Sunan Kalijaga dengan
symbol jarring laba-laba. Dimana klasifikasi dari setiap tingkatan perkembangan
ilmu pengetahuan berdasarkan atas perkembangan ilmu pengetahuan dalam
perspektif sejarah Islam. Dapat dilihat dalam gambar jaring laba-laba tersebut, di
tengah-tengah sebagai sumber adalah Al-Qur‟an dan Sunnah hingga pada 5
tingkatan lebih luas. Ide tersebut diwujudkan di antaranya dalam bukti fisik
artefak bangunan di UIN Sunan Kalijaga yang saling terkait antara satu gedung
fakultas dengan gedung fakultas lainnya, sebagai gambaran kesatuan dan
keterkaitan antara satu ilmu pengetahuan dan pengetahuan yang lain.
Hal ini menjadi menarik, jika para sarjana mengetahui dinamika
perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Sehingga para cendekiawan yang
disiapkan oleh lembaga pendidikan Islam memahami dengan baik “sangkan
paraning dumadi” dari ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam di masa-masa
3
awal hingga saat ini. Dengan pengetahuan tersebut, para pengelola lembaga,
pendidik, dan para stakeholder memahami arah dan tujuan yang akan dicapai
umat Islam.
2. Fokus Kajian
Dengan latarbelakang tersebut, diharapkan kajian ini memberikan
gambaran tentang hal-hal berikut:
a. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam
b. Hakikat ilmu pengetahuan dalam Islam
c. Pembagian ilmu pengetahuan dalam Islam
d. Tokoh-tokoh perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam
B. Pembahasan
1. Sejarah Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dalam Islam
Masa Rasulullah dan Para Sahabat
Ilmu pengetahuan menjadi perhatian yang sangat besar pada masa
Rasulullah Saw. Perhatian tersebut diwujudkan dalam berbagai tindakan di
antaranya adalah:
a. Bahwa wahyu yang pertama kali adalah iqra’ yang berarti bacalah dengan
nama Tuhanmu yang menciptakan alam semesta, memiliki pemahaman
untuk senantiasa belajar dan mencari tahu hakikat dari seluruh alam
semesta yang diciptakan-Nya. Dan membaca itulah sebagai kunci untuk
membuka ilmu pengetahuan.
b. Masyarakat Arab pada saat itu memiliki kelebihan dalam kuatnya hafalan.
Rasulullah Saw menggunakan keunggulan tersebut, dengan
memerintahkan kepada sebagian sahabat untuk menghafal al-Qur‟an.
Tidak hanya itu, beberapa sahabat menyimak, memperhatikan, dan
menanyakan tentang segala sesuatu untuk diketahui kepada Rasulullah
Saw atas apa yang ada pada ayat-ayat Al-Qur‟an. Kelak ucapan, tindakan,
dan keputusan Rasulullah Saw, menjadi sandaran dan sumber bagi ilmu
pengetahuan. Demikian itu sudah ditegaskan dalam Al-Qur‟an bahwa pada
4
dirinya adalah suri tauladan, dan dalam suatu riwayat disebutkan bahwa
prilaku Rasulullah Saw adalah Al-Qur‟an
c. Rasulullah Saw memerintahkan untuk para sahabat menuliskan Al-Qur‟an
selain dengan menghafalkannya. Dengan keterbatasan para sahabat yang
pandai menulis dan membaca, maka saat terdapat tawanan setelah perang
Badar, tawanan yang sanggup untuk membaca dan menulis tebusannya
adalah mengajarkan 10 orang tulis dan baca.
d. Pada masa itu bangsa Arab tidak memiliki sumber ilmu pengetahuan.
Dengan masuknya agama Islam, ilmu pengetahuan bersumber pada Al-
Qur‟an dan Sunnah Nabi. Di dalam Al-Qur‟an terdapat berbagai kisah
Nabi terdahulu, Hukum-hukum, Sifat-sifat Allah Swt, dan Pengetahuan
tentang alam semesta. Rasulullah melengkapinya dengan penjelasan-
penjelasan yang sesuai untuk zaman itu.
Setelah wafatnya Nabi Saw, Sahabat-sahabat Nabi menjadi sumber
rujukan ilmu pengetahuan. Orang-orang yang ingin mendapatkan ilmu
pengetahuan mereka datang kepada para Sahabat. Para sahabat tersebut
menyampaikan apa yang didapatkan dan difahaminya dari Nabi. Penjelasan para
sahabat atas Al-Qur‟an itulah yang disebut tafsir. Pada saat itu ilmu yang
berkembang adalah ilmu tafsir, qiraat, fiqh, qada (kehakiman), faraidh, dan ilmu
hadits. Sampai disini kiranya dapat dimengerti bahwa antara tafsir dan hadits
merupakan satu kesatuan, atau lebih tepat dikatakan tafsir merupakan bagian dari
hadits pada periode ini.2
Diantara para sahabat yang pandai atau ahli adalah Umar bin Khattab, Ali
bin Abi Thalib, Zaid bin Tsabit, Ibnu Mas‟ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan
Aisyah.
Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, Islam menyebar luas.
Penyebaran tersebut berakibat pada semakin bertambahnya jumlah muslimin
dengan berbagai latar belakang, bercampurnya antara bangsa Arab dan „Ajam,
pertemuan dengan berbagai budaya dan peradaban di daerah penaklukan,
memerlukan tenaga da‟wah yang menjelaskan urusan-urusan agama pada
2 Harun Nasution, Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran, (Bandung: Mizan, 1998), hal. 306
5
masyarakat baru tersebut. Keragaman masyarakat muslim berdampak pada
tuntutan untuk memberikan penjelasan yang dialogis dengan kalangan muslim
yang masih baru.
Diantara Peristiwa-peristiwa ilmiah yang penting pada masa
khulafaurrasyidin, yang memberikan dampak pada perkembangan ilmu
pengetahuan pada masa-masa berikutnya adalah:
a. Pengumpulan Al-Qur‟an yang merupakan hasil dari usaha dua khalifah
Abu Bakar dan Utsman sebab ditakutkan penghafal-penghafal al-Qur‟an
nanti akan meninggal dunia dan hilanglah Al-Qur‟an bersama mereka.
b. Pengumpulan apa yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw baik perkataan,
perbuatan, ataupun keputusan supaya jangan hilang atau dipalsukan orang.
c. Permulaan pembukuan ilmu nahwu¸sebaba sudah mulai muncul dialek
(accent) yang aneh di kalangan orang-orang peranakan.
d. Para ulama mempelopori usaha penafsiran Al-Qur‟an ketika ternyata rasa
seni sastra Arab di kalangan orang-orang yang baru masuk Islam itu mulai
melemah.3
Berbagai usaha tersebut menjadi dasar atas perkembangan ilmu pengetahuan di
masa yang akan datang. Al-Qur‟an yang telah dikumpulkan secara terpisah dari
Hadits Nabi, memberikan kejelasan mana yang menjadi wahyu Allah Swt. dan
sabda Rasulullah Saw. Dengan demikian, Al-Qur‟an dapat dijadikan dasar tentang
pengembangan kajian ilmu bahasa, karena Al-Qur‟an jauh dari kesalahan bahasa.
Demikian juga halnya dalam Hadits Nabi Saw. yang darinya berkembang ulumul
hadits.
Masa Dinasti Umawiyyah
Sebelum munculnya dinasti Umawiyyah terjadi dua cobaan besar pada
umat Islam, pertama terbunuhnya khalifah ke-3 Utsman bin Affan dan para
sahabat menuntut untuk mencari tahu dalang dari pembunuhan tersebut. Kedua,
timbulnya perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dengan Mu‟awiyah bin Abi
3 Hasan Langgulung, Pendidikan Islam Menghadapi Abad ke 21, (Jakarta: Radar Jaya, 1988), hal.
6-7
6
Sufyan, dalam kejadian itu terdapat apa yang dikenal dengan istilah tahkim. Yang
pada akhirnya menyebabkan Ali bin Abi terbunuh dan muncullah kerajaan
Umawiyah di bawah Mu‟awiyah bin Abi Sufyan.
Dari perselisihan tersebut muncul berbagai firqah dalam aqidah, seperti
Khawarij, Syi‟ah, Ahlu Sunnah, Jabariyah, Qadariyah, dan lain-lain. Dalam
rangka memberikan status atas keputusan khalifah. Setelah kondisi aman, ilmu
pengetahuan pun berkembang dan ilmu pengetahuan pun disusun secara
sistematis, untuk ukuran saat itu. Sehingga pembidangan ilmu tersusun sebagai
berikut:
a. Ilmu pengetahuan bidang agama yaitu, segala ilmu yang bersumber dari
Al-Qur‟an dan Hadits.
b. Ilmu pengetahuan bidang sejarah yaitu, segala ilmu yang membahas
tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat.
c. Ilmu pengetahuan bidang bahasa yaitu, segala ilmu yang mempelajari
bahasa, nahwu, sharaf, dan lain-lain
d. Ilmu pengetahuan bidang filsafat yaitu, segala ilmu yang pada umumnya
berasal dari bangsa asing seperti ilmu mantiq, kedokteran, kimia,
astronomi, ilmu hitung, dan ilmu lain yang berhubungan dengan ilmu-ilmu
tersebut.4
Sampai pada masa dinasti umawiyah ini belum banyak varian kajian ilmu
pengetahuan, dikarenakan gerakan terjemah belum menjadi fokus yang besar.
Namun yang patut dicatat bahwa pada dinasti bani umawiyah kemajuan padan
bidang bahasa telah sampai pada kemapanannya.
Berkembangnya berbagai ilmu pengetahuan tersebut tidak terbatas pada
aspek ontology dari ilmu-ilmu tersebut. Para ilmuwan muslim juga turut
mengembangkan pada aspek epistimologi dan aksiologi dari ilmu-ilmu tersebut.
Sehingga yang terjadi adalah tidak terbatas pada penulisan dan pemindahan ilmu,
tetapi juga terjadi proses analisis dari ilmu-ilmu yang baru, dan ilmu-ilmu
pengembangan.
4 Musyrifah Sunanto, Sejarah IslamKlasik; Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam, (Jakarta:
Kencana, 2004), hal. 42
7
Masa Dinasti Abbasiyah
Kesuksesan Dinasti Bani Umawiyah yang dapat menaklukkan wilayah-
wilayah kerajaan Romawi dan Persia, segera disusul dengan prestasi yang lebih
hebat lagi dalam penaklukan bidang ilmu pada abad berikutnya. Penelaahan ilmu
yang telah dilakukan pada zaman Bani Umawiyah menjadi usaha yang
dioptimalkan pada Bani Abbasiyah.
Gerakan membangun ilmu besar-besaran dirintis oleh khalifah Ja‟far al-
Mansur. Setelah mendirikan kota Bagdad dan menjadikannya ibu kota Negara. Ia
menarik ulama dan para ahli dari berbagai daerah untuk datang dan tinggal di
Baghdad. Ia merangsang usaha pembukuan ilmu agama, seperti fiqh, tafsir,
tauhid, hadits, atau ilmu lain seperti ilmu bahasa dan sejarah. Akan tetapi yang
lebih mendapat perhatian adalah penerjemahan ilmu yang berasal dari luar.5
Dengan pertemuannya dengan berbagai peradaban dan kebudayaan
termasuk di dalamnya adalah peradaban Yunani yang tercermin dalam peradaban
Romawi dan Persia. Ilmu-ilmu semakin berkembang, selain itu juga detail
menjadi beragam. Diantara ilmu-ilmu yang dikelola dan berkembang pada Dinasti
Bani Abbasiyah adalah:
A. Pengetahuan agama dan Syar‟iyah: Ilmu tafsir Al-Qur‟an, Ilmu Bacaan,
Ilmu Hadits, Ilmu Musthalahul Hadits, Imu Fiqh, Ilmu Ushul Fiqh, Ilmu
Kalam, dan Ilmu Tasawuf.
B. Ilmu-Ilmu Bahasa dan Sastera: Ilmu Bahasa, Ilmu Nahwu, Sharaf, dan
„Arudh, Ilmu Sastra, Ilmu Balaghah, dan Ilmu Kritik Sastra.
C. Ilmu-ilmu Sejarah dan Sosial: Ilmu Sirah (Peperangan, dan Biografi), ilmu
Sejarah politik dan sosial, Ilmu Jiwa (Pendidikan, Akhlak, Sosiologi,
Ekonomi, Politik, dan Tatalaksana), Ilmu Geografi dan Perencanaan Kota.
D. Ilmu-ilmu Falsafah, Logika, Debat, dan Diskusi.
E. Ilmu-ilmu Bahts; Ilmu Matematika, Ilmu Falak, dan Ilmu Musik
F. Ilmu Kealaman dan Eksperimental; Ilmu Kimia, Ilmu Fisika, dan Ilmu
Biologi.
5 Musyrifah Sunanto, Sejarah IslamKlasik;hal. 57
8
G. Ilmu-ilmu Terapan Praktis; Ilmu Kedokteran, Ilmu Farmasi, dan Ilmu
Pertanian.6
Pada masa tersebut muncul banyak tokoh-tokoh dan ahli dalam berbagai
ilmu pengetahuan. Menariknya, adalah dalam satu tokoh tertentu memiliki
penguasaan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan yang lain, utamanya adalah
ilmu-ilmu agama. Artinya bahwa pada saat tersebut tidak terjadi dikotomi ilmu
pengetahuan. Sehingga model kesatuan ilmu pengetahuan yang bersumber dari
Al-Qur‟an dan Sunnah meberikan motivasi untuk membaca dan menganalisa lebih
dalam akan makna yang terkandung dalam Islam.
Masa Kemunduran
Zaman kemunduran diungkapkan oleh Musyrifah Sunanto terjadi ketika
kekuasaan keturunana Mongol berakhir pada tahun 1525. Zaman ini diawali
dengan kemajuan bidang politik tiga kerajaan bear: Usmaniyah, Shafawiyah,
Mughol, India, sesudah itu seluruh Dunia Islam mundur secara berangsur-angsur
dan akhirnya jatuh di bawah kekuasaan Barat.7 Ciri-ciri dari masa ini adalah:
Pintu ijtihad seakan-akan tertutup, Putusnya hubungan antar Ulama, dan Zaman
ikhtiar dan Syarah.
Pemindahan pemikiran rasional dan ilmu pengetahuan yang berkembang
dalam Islam ke Eropa, menurut Harun Nasution melalui 3 jalur:
a. Andalus yang mempunyai universitas-universitas yang dikunjungi oleh
orang-orang Eropa, seperti Michael Scot, Robert Chester, Adelard Barth,
Gerard dari Cremona dan lain-lain. Toledo mempunyai peranan penting
dalam hal ini.
b. Sisilia pernah dikuasai oleh Islam dari tahun 831 sampai tahun 1091,
ketika pulau itu jatuh ke tangan kaum Norman di bawah pimpinan Roger.
Di pulau ini pengetahuan juga berkembang di tangan ulama-ulama Islam,
bukan pada zaman kekuasaan Islam saja, tetapi juga pada zaman
kekuasaan Norman. Sebagaimana halnya di Toledo, Spanyol, Palermo, ibu
6 Hasan Langgulung, Pendidikan Islam, hal. 11-12
7 Musyrifah Sunanto, Sejarah Islam Klasik, hal. 88
9
kota Sisilia terdapat pula kegiatan penerjemahan buku-buku ulama ke
dalam Bahasa Latin. Di sini buku-buku yang ditejemahkan itu dibawa ke
Eropa bagian Selatan, suatu hal yang melahirkan Renaissans Itali.
c. Perang Salib, bila diperbandingkan dengan kedua jalur di atas, peranannya
dalam memindahkan ilmu pengetahuan Islam ke Barat tidak besar. Tetapi,
di Suriah terjadi juga penerjemahan buku-buku, Rumah-rumah sakit, dan
pemandian-pemanidian umum, yang banyak dijumpai orang-orang Barat
di Suriah pada waktu itu, muncul pula di Eropa.8
Perpindahan ilmu pengetahuan ke Eropa merupakan suatu proses dialogis
antara masyarakat muslim dengan masyarakat Eropa. Yang pada saat itu,
masyarakat muslim dengan daerah kekuasaannya mencakup beberapa daerah di
Andalusia dan Sisilia memberikan kesempatan kepada masyarakat Eropa untuk
belajar ilmu yang dimiliki oleh masyarakat muslim. Proses transformasi ilmu ini
menjadi dasar atas kebangkitan masyarakat Eropa yang dikenal dengan
Renaissance. Beberapa peneliti Barat mengungkapkan akan hutang budi
masyarakat Eropa terhadap peradaban Islam yang mengembangkan ilmu
pengetahuan dengan damai dan toleran.
Masa Kebangkitan
Sains dalam pengertiannya yang modern adalah pengembangan dari
filsafat alam yang merupakan bagian dari filsafat yang menyeluruh dalam
khazanah keilmuan Yunani. Namun, filsafat Yunani terlalu deduktif, yang lebih
berdasarkan pada pemikiran spekulatif.9 Barat yang mewarisi hal tersebut
memisahkannya dengan agama, terlebih kegagalan agama Kristen dalam
mendiskusikan antara ilmu dan agama. Yang terjadi adalah sekulerisasi sains yang
diikuti sekularisasi politik ternyata melahirkan peradaban Barat yang kuat secara
ekonomi militer, berbasis sains dan teknologi.
Sekularisasi tersebut menimbulkan masalah. Masalahnya adalah dampak
negative pada kehidupan manusia dan lingkungannya. Dan salah satu dampaknya
8 Harun Nasution, Islam Rasional, hal. 301-302
9 Armahedi Mahzar, Revolusi Integralisme Islam: Merumuskan Paradigma Sanis dan Teknologi
Islami, (Bandung: Mizan, 2004), hal. 210
10
adalah ketidakharmonisan antara sains dan agama. Dalam ketidakharmonisan
tersebut yang terjadi adalah konflik dan independensi. Meminjam istilah Ian G.
Barbour, tentang kesenjangan antara Ilmu dan agama pada empat tahapan yaitu
konflik, Independensi, Dialog, dan Integrasi.10
Kritik dimunculkan oleh Sayyed Hossein Nasr yang menekankan
perbedaan antara sains Islam tradisional pada masa kejayaan Islam yang
paradigmanya sama sekali berbeda dengan sains Barat modern yang sekuler.
Sayyid M. Naquib Al-Attas, Ismail Raji Al-Faruqi, diantaranya yang
memunculkan paradigma baru yaitu Islamisasi Ilmu.
Integrasi sains dan agama dapat dilakukan dengan mengambil inti filosofis
ilmu-ilmu keagamaan fundamental Islam sebagai paradigm sains masa depan. Inti
filosofis itu adalah adanya hirarki epistimologis, aksiologis, kosmologis, dan
teologis yang berkesesuaian dengan hierarki integralisme; materi, energy,
informasi, nilai-nilai dan sumber. Proses integrasi ini dapat dianggap sebagai
bagian dari proses Islamisasi peradaban masa depan.11
2. Hakikat Ilmu Pengetahuan Dalam Islam
Syamsuddin Arif menyebutkan beberapa definisi ilmu menurut para
ulama‟ sebagai berikut:
a. Al-Raghib al-Isfahani (w.443/1060), dalam karyanya Kamus Istilah
Qur’an, ilmu didefinisikan sebagai “persepsi suatu hal dalam hakikatnya”
(al-‘ilm idrak al-Shay’ bi-haqiqatihi).
b. Imam Al-Ghazali (w.505/1111), yang memberikan definisi ilmu
“pengenalan sesuatu atas dirinya” (ma’rifat al-Shay ‘ala ma huwa bihi).
c. Athir al-Din al-Abhari (w.663/1264), yang memberikan definisi ilmu
adalah menghampirnya “gambar” suatu benda dalam pikiran. Yang
demikian pula Ibnu Sina (w.428/1037) mendefinisikan.
10
Ian G. Barbour, Juru Bicara Tuhan: Antara Sains dan Agama, (Bandung : Mizan, 2002), hal.
39-42 11
Rasmianto, Relasi Agama dan Sains dalam Studi Islam di PTAI, dalam Ulul Albab Jurnal Studi
Islam, Vol.9. No. 1. 2008, hal. 18
11
d. Al-Sharif al-Jurjani (w.816/1413) dalam bukunya Ta’rifat mendefinisikan
ilmu sebagai tibanya minda12
pada makna sesuatu.
e. Syed M. Naquib Al-Attas dalam The Concept of Education in Islam,
menyebutkan ilmu adalah “tibanya makna dalam jiwa, sekaligus tibanya
jiwa pada makna”.
f. Ibnu „Arabi (w.638/1240) mendefinisikan ilmu sebagai penerimaan mental
atas (ilmu tentang) segala hal dalam batas dirinya apa adanya (tahsil al-
qalb amran ma ‘ala had ma huwa ‘alayhi dhalika al-amr).13
Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibany dalam “Falsafah at-Tarbiyah
al-Islamiyah” menyebutkan lima prinsip dasar teori pengetahuan dalam pemikiran
Islam, yaitu; Pertama, Percaya pada pentingnya pengetahuan (makrifah) sebagai
salah satu tujuan pokok; Kedua, Percaya bahwa pengetahuan manusia adalah
maklumat, fikiran-fikiran, pengertian-pengertian, tafsiran-tafsiran yang diyakini,
hukum-hukum, tanggapan-tanggapan, gambaran yang pasti yang kita capai
tentang sesuatu sebagai akibat kita menggunakan panca indra kita, atau akal kita,
atau kedua-duanya sekali, atau sebagai akibat dari suatu yang kita peroleh melalui
ilham, atau perasaan, atau penglihatan dengan mata, atau melalui kasyaf, atau
melalui ajaran agama dan diturunkan melalui wahyu ilahi; Ketiga, Percaya bahwa
pengetahuan manusia berbeda mutu dan nilainya sesuai dengan perkara, tujuan
dan jalannya. Keempat, Percaya bahwa pengetahuan manusia itu mempunyai
sumber yang bermacam-macam, yang dalam Islam merujuk pada lima sumber
pokok yaitu: indera, akal, intuisi, ilham, dan wahyu ilahi. Kelima, percaya bahwa
pengetahuan terlepas dari akal yang mengamatinya dan tersimpan di dalamnya,
dan juga benda-benda mempunyai fakta-fakta yang tetap dan mempunyai wujud
yang bebas dalam fikiran kita. Keenami, Percaya bahwa pengetahuan sebenarnya
ialah yang cukup keyakinan dan pasti, merendah diri di depan keagungan Allah
dan luasnya ilmu-Nya, sesuai dengan jiwa agama dan prinsip akhlak yang mulia
yang ditentukannya, menimbulkan rasa tenang dan tentram dalam jiwa, tepat dan
12
Minda yaitu keadaan di mana sesuatu itu tidak lagi asing bagi orang tersebut karena dikenali
oleh minda orang tersebut. 13
Syamsuddin Amir, Mendefinisiak dan Memetakan Ilmu, dalam Adian Husaini, et.al. Filsafat
Ilmu: Perspektif Barat dan Islam, (Depok: Gema Insani Press, 2013), hal. 75-78
12
obyektif, dan meneguhkan amal yang baik, pengalaman yang Berjaya dan
memudahkan jalan kemajuan dan kekuatan masyarakat.14
Dari berbagai definisi tersebut dapat ditarik garis lurus, bahwa ilmu
pengetahuan dalam perspektif Islam memiliki dua kandungan makna yaitu Ilmu
pengetahuan sebagai objek, dan ilmu pengetahuan sebagai proses. Mengenai
proses mendapatkan ilmu pengetahuan, para ilmuwan muslim berhati-hati dalam
context of discovery dan context of justifikasi dari mendalami ilmu pengetahuan.
Ontologi
Di dalam Al-Qur‟an, Allah Swt memerintahkan kepada manusia untuk
menggunakan akal. Dengan akal tersebut manusia dapat meneliti dan mencari
tahu bagaimana alam semesta. Perintah untuk menggunakan akal, dan meneliti
alam semesta, menuntun manusia untuk mendapatkan pengetahuan. Demikian itu
dapat ditemui dalam banyak ayat-ayat Al-Qur‟an dan Sunnah.
Quraish Shihab menyebutkan bahwa kata ilmu dengan berbagai bentuknya
terulang 854 kali dalam Al-Qur‟an. Kata ini digunakan dalam arti proses
pencapaian pengetahuan dan objek pengetahuan. Objek ilmu mencakup alam
materi dan alam nonmateri. Mengutip pendapat sufi memperkenalkan ilmu yang
mereka sebut al-hadharat al-Ilahiyah al-Khams (lima kehadiran ilahi), untuk
menggambarkan hierarki keseluruhan realitas wujud. Lima hal tersebut adalah; (1)
alam nasut (alam materi), (2) alam malakut (alam kejiwaan), (3) alam jabarut
(alam ruh), (4) alam lahut (sifat-sifat ilahiyah), dan (5) alam hahut (wujud zat
ilahi).15
Dinar Dewi Kania menyebutkan bahwa objek dari pada ilmu yang
bersumber pada al-Qur‟an yaitu alam metafisik (‘alam al-Ghayb), dan alam fisik
yang tampak (álam al-Syahadah).16
Dengan dua jenis alam tersebut,
menyebabkan ada dua jenis ilmu yang disebut dalam Al-Qur‟an, yaitu ilmu
14
Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibany, Falsafah at-Tarbiyah al-Islamiyah, alih bahasa
Hasan Langgulung, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hal. 259-310 15
Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat, (Bandung:
Mizan, 2012), hal. 574 16
Dinar Dewi Kania, Objek Ilmu dan Sumber-Sumber Ilmu, dalam Adian Husaini, et.al. Filsafat
Ilmu: Perspektif Barat dan Islam, (Depok: Gema Insani Press, 2013), hal.88
13
tentang alam metafisik (ma’rifah) dan ilmu tentang alam fisik (‘ilm/Science).
Menurut pendapatnya, meskipun al-Qur‟an menyebutkan perbedaan antara alam
metafisik dan fisik, namun keduanya tidak dapat dilepaskan satu dengan lainnya,
karena tujuan untuk mempelajari alam fisik adalah menunjukkan kepada ilmu
tentang alam metafisik.
Abu Hamid al-Ghazali memandang bahwa ilmu yang wajib dicari menurut
agama adalah terbatas pada pelaksanaan kewajiban-kewajiban syari‟at Islam yang
harus diketahui dengan pasti,17
yang mengacu pada ilmu tentang jalan menuju
kehidupan sesudah kematian, di sini dikategorikannya sebagai fardhu ‘ain. Yang
kemudian dibaginya dengan dimensi eksoterik (‘ilm mu’amalah) dan esoteric
(‘ilm al-mukasyafah).18
Sedangkan ilmu-ilmu yang termasuk dengan fardhu kifayah
dikategorikannya menjadi dua ilmu yaitu “ilmu agama” dan “ilmu nonagama”.
Dengan ilmu agama (‘ulum syar’i), beliau maksudkan kelompok ilmu yang
diajarkan lewat ajaran-ajaran Nabi dan Wahyu. Sedangkan yang lainnya adalah
kelompok “ilmu nonagama”. Ilmu nonagama juga diklasifikasikan menjadi tiga
yaitu terpuji (Mahmud), dibolehkan (Mubah), dan tercela (Madzmum).19
Terdapat
tiga derajat perolehan pengetahuan yaitu terbatas (iqtishar), cukup (iqtishad), dan
lanjut (istiqsha).20
Di sini pembatasan diberikan oleh Al-Ghazali dimana untuk
ilmu-ilmu fardhu ‘ain wajib diketahui walaupun dalam batas iqtishar, sedangkan
dalam ilmu fardhu kifayah tidak boleh lebih dari iqtishad. Demikian itu
dimaksudkan karena ilmu-ilmu tersebut sangat luas, dan usia manusia terbatas,
sehingga dikhawatirkan melalaikan tujuan akhirat.
Mahdi Ghulsyani berpendapat bahwa kata “ilmu” sebagaimana yanga ada
di dalam Al-Qur‟an dan Sunnah nampak di dalam makna generiknya (umum)
ketimbang merujuk secara ekslusif kepada studi agama-agama. Di dalam Islam,
batasan untuk mencari ilmu hanyalah bahwa orang-orang Islam harus menuntut
17
Mahdi Ghulsyani, Filsafat Sains Menurut Al-Qur’an, alih bahasa Agus Efendi, (Bandung:
Mizan, 1998), hal. 40 18
Osman Bakar, Hirarki Ilmu, hal. 238 19
Mahdi Ghulsyani, Filsafat-Sains, hal. 41 20
Osman Bakar, Hirarki Ilmu, hal. 239
14
ilmu yang berguna. Islam hanya melarang orang-orang Islam dari menerjunkan
dirinya dalam mencari suatu cabang-cabang ilmu yang bahayanya lebih besar dari
manfaatnya.21
Artinya adalah bahwa mempelajari ilmu tidak terbatas pada ilmu-
ilmu syari‟ah saja, melainkan dalam berbagai ilmu pengetahuan. Meskipun tidak
semua orang harus mempelajari ilmu-ilmu alam, karena tidak semua diberikan
kelebihan untuk mengetahui dan memahami alam semesta.
Epistimologi
Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan pada umumnya terdapat dua jalan.
Yaitu melalui usaha manusia, dan ilmu yang diberikan oleh Allah Swt.
Pengetahuan yang diperoleh manusia melalui usaha ada empat jenis, yaitu;
(1) Pengetahuan empiris yang diperoleh melalui indera, (2) Pengetahuan sains
yang diperoleh melalui indera dan akal, (3) Pengetahuan filsafat yang diperoleh
melalui akal, dan (4) Pengetahuan intuisi yang diperoleh melalui qalb (hati).
Sedangkan pengetahuan yang diberikan Allah Swt berupa (1) Wahyu yang
disampaikan kepada para Rasul, (2) Ilham yang diterima oleh akal manusia, dan
(3) Hidayah yang diterima oleh qalb manusia.22
Quraish Shihab menambahkan
bahwa selain dengan mata, telinga, dan pikiran sebagai sarana meraih
pengetahuan, Al-Qur‟an pun menggarisbawahi pentingnya peranan kesucian
hati.23
Mahdi Ghulsyani menyebutkan bahwa untuk memahami Alam dapat
dilakukan melalui tiga hal, yaitu: Pertama, Indera-indera eksternal (dengan indera
ini pengamatan dan eksperimen dapat dilakukan); Kedua, Intelek yang tak
terkotori oleh sifat-sifat buruk (yang menguasai kehendak-kehendak dan
khayalan-khayalan, dan bebas dari peniruan buta); Ketiga, Wahyu dan inspirasi.24
Yang dimaksud dengan intelek yaitu hati (qalb), yang dapat digunakan sebagai
alat untuk mendapatkan persepsi.
21
Mahdi Ghulsyani, Filsafat-Sains, hal. 47 22
Ramayulis dan Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam; Telaah Sistemis Pendidikian dan
Pemikiran Para Tokohnya, (Bandung: Kalam Mulia, 2009), hal. 78 23
Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an, hal. 576 24
Mahdi Ghulsyani, Filsafat-Sains, hal. 84
15
Al-Ghazali menunjukkan dua cara berbeda dalam mendapatkan
pengetahuan. Pengetahuan yang dihadirkan bersifat langsung, serta-merta,
suprarasional, intuitif, dan kontemplatif disebut sebagai pengetahuan yang
dihadirkan (ilm hudhuuri) dengan kata lain Al-Ghazali menyebutnya ‘ilm alduni
dan ‘ilm al-mukasyafah. Jenis pengetahuan lainnya yang diperoleh oleh pikiran
melalui bantuan konsep-konsep antara disebut pengetahuan capaian atau
pengetahuan yang diperoleh (ilm hushuuli).25
Dalam pandangan Al-Farabi perkembangan pengindraan jiwa manusia
melalui lima tahap yaitu: pertumbuhan, mengindra (al-Quwwah al-Hassah),
bernafsu (al-Quwwah al-nuzuuliyah), mengkhayal, dan berfikir.26
Kelima-limanya
membentuk hierarki, setiap tahap pengindraan hadir demi tahap di atasnya, dan
yang tertinggi adalah daya berfikir.
Struktur tritunggal badan (corpus), jiwa (anima, psyche), dan ruh
(spiritus), yang diidentikkan dengan daya mengindra, daya mengkhayal, dan daya
berpikir juga sesuai dengan struktur tritunggal dunia ragawi, jiwa, dan ruhani
kosmos.27
Pada prinsipnya terdapat berbagai istilah dalam epistimologi Islam, dan
setiap ulama memiliki istilah-istilah tersendiri. Seperti Al-Farabi dengan
metodenya al-Ittishol, Al-Ghazali dengan metodenya al-Mukaasyafah, Quthb ad-
Diin al-Syirozi dengan metodenya Hikmatul Isyraq atau yang sering dikenal
dengan ilmuinasi, al-Hallaj dengan wihdatul wujud, dan Ibnu „Arabi dengan al-
Ittihaad. Dan beberapa ulama‟ lain. Yang pada intinya, adalah ilmu yang
sedemikian luasnya mencakup tiga teori umum yaitu bayany, burhany, dan
‘irfany.
Epistimologi bayany adalah suatu cara mendapatkan pengetahuan yang
bersumber pada pemahaman yang komprehensip terhadap teks. Teks tersebut
dapat difahami secara langsung, atau bisa juga melalui tafsir ataupun takwil. Pada
intinya, model epistimolgi bayany lebih menekankan pada pemahaman teks.
25
Osman Bakar, Hirarki Ilmu, hal. 221 26
Osman Bakar, Hirarki Ilmu, hal. 66 27
Osman Bakar, Hirarki Ilmu, hal. 66
16
Epositmologi burhany adalah suatu cara memperoleh pengetahuan dengan
pendekatan rasional, artinya bahwa pengetahuan yang didapati adalah berdasarkan
struktur nalar logika, dimana data yang ada dikumpulkan dan disusun secara
sistematis, kemudian diujikan kebenarannya. Epistimologi burhany lebih bersifat
rasionalistis.
Sedangkan epistimologi irfani yaitu suatu cara mendapatkan pengetahuan
dengan pendekatan ma’rifah, yaitu dengan berbasiskan pengalaman
keberagamaan seseorang yang darinya ia mendapatkan intuisi “kasyf” dengan
Tuhan. Dan pada epistimologi irfani lebih dekat dengan penjelasan yang
bersumber pada pengalaman.
Ketiga pendekatan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-
masing. Namun dengan tidak mengurangi nilai kelebihannya, bahwa setiap model
epistimologi dapat diaplikasikan pada satu ilmu tertentu dan terkadang tidak dapat
diaplikasikan dengan cara yang sama terhadap ilmu yang lain. Sebagai contoh,
dalam kajian bahasa yang bersumber pada teks, tentuk lebih dekat dengan
menggunakan metode bayany daripada burhany, demikian juga untuk ilmu-ilmu
yang lain. Dengan kata lain, tiga model epistimologi ini dapat digunakan sesuai
dengan karakter dari ilmu pengetahuan yang ingin di dalami.
Aksiologi
Fungsi dari ilmu pengetahuan secara umum adalah (1) untuk berubudiyah
kepada Allah Swt, (2) untuk membedakan yang hak dengan yang bathil, dan (3)
sebagai modal untuk mencapai kebenaran dan kebahagiaan hidup di dunia dan di
akhirat.28
Mahdi Ghulsyani berpendapat bahwa ilmu tersebut dianggap berguna
berdasarkan pemahaman bahwa tujuan manusia adalah mendekatkan diri kepada
Allah dan mendapatkan ridha-Nya; aktivitas-aktivitasnya harus difokuskan pada
arah ini. Segala sesuatu yang mendekatkan kepada Tuhan atau petunjuk-petunjuk
pada arah tersebut adalah terpuji. Sehingga, ilmu hanya berguna jika dijadikan alat
untuk mendapatkan pengetahuan tentang Allah, keridhaan dan kedekatan kepada-
28
Ramayulis dan Syamsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, hal. 80
17
Nya. Jika tidak, ilmu itu sendiri akan menjadi penghalang yang besar (hijab al-
akbar), apakah ia tercakup dalam ilmu-ilmu kealaman maupun ilmu-ilmu
syari‟ah.29
3. Pembagian Ilmu Pengetahuan
Al-Farabi
Al-Farabi dalam memberikan gambaran pemeringkatan atau hirarki dalam
ilmu pengetahuan didasari oleh kriteria-kriteria berikut: Pertama, kemuliaan
materi sujek (Syaraf al-maudhu’i), berasal dari prinsip fundamental ontologi,
yaitu bahwa dunia wujud tersusun secara hierarkis. Kedua, kedalaman bukti-bukti
(istisqha al-Barahiin), didasarkan atas pandangan tentang sistematika pernyataan
kebenaran dalam berbagai ilmu yang ditandai oleh perbedaan derajat kejelasan
dan keyakinan. Ketiga, tentang besarnya manfaat („izham al-Jadwa) dari ilmu
yang bersangkutan, didasarkan pada fakta bahwa kebutuhan praktis dan spiritual
yang berkaitan dengan aspek kehendak jiwa juga tersusun secara hirarkis.30
Selain dengan mendasari hirarki ilmu pengetahuan dengan pendekatan
epistimologis, Al-Farabi juga mendasarinya dengan daya jiwa yang ada pada
manusia, yang membaginya menjadi lima tahap, yaitu: pertumbuhan, mengindra
(al-quwwat al-hassah), bernafsu (al-quwwat al-nuzuuliyah), mengkhayal dan
berpikir.31
Dengan tiga hal tersebut dapat dimengerti bahwa jiwa manusia dalam
mendapatkan pengetahuan, menurut pendapat al-Farabi melalui tiga unsur yaitu
badan (jism), jiwa (nafs), dan ruh (‘aql). Tiga unsur tersebut diidentikkan dengan
tiga tindakan yaitu mengindra, mengkhayal, dan berfikir.
Al-Farabi membagi ilmu pengetahuan secara berurut dengan tingkatannya
pada enam tingkatan, yaitu:
a. Ilmu Bahasa (‘ilm al-Lisaan)
29
Mahdi Ghulsyani, Filsafat-Sains, hal. 55 30
Osman Bakar, Hirarki Ilmu, hal. 65 31
Osman Bakar, Hirarki Ilmu, hal. 67
18
b. Logika (‘ilm al-manthiq)
c. Ilmu-ilmu Matematis atau propaedetik (ulum al-ta’alim), di dalamnya
terdapat Aritmatika, Geometri, Optika, Ilmu perbintangan, Musik, Ilmu
tentang berat, dan Teknik
d. Fisika atau ilmu kealaman (al-‘Ilmu ath-Thabi’i)
e. Metafisika (al-‘Ilm al-Ilahy)
f. Ilmu Politik (al-‘ilm al-madani), yurisprudensi (‘ilm al-fiqh) dan teologi
dialektis (‘ilm al-kalam)32
Dari pembagian oleh al-Farabi sebagaimana tersebut di atas, dapat
dimengerti bahwa susunan antara enam tingkatan tersebut dibagi berdasarkan
dengan kekuatan manusia dalam mendapatkan pengetahuan sebagaimana yang
dipersepsikan, yaitu mengindra, mengkhayal, dan berfikir.
Al-Ghazali
Osman Bakar mengklasifikasikan ilmu pengetahuan dalam perspektif Al-
Ghazali dengan merujuk pada The Book of Knowledge (Kitab ilmu) dari Ihya’
ulumiddin dan Al-Risaalat al-Laaduniyah. Dan dua karya sebagai penunjang
yaitu The Jewels of the Qur’an (Mutiara Al-Qur’an) dan Mizan al-‘amal
(Timbangan Amal). Dalam karya-karya ini Al-Ghazali menyebutkan empat
sistem klasifikasi yang berbeda:
a. Pembagian ilmu-ilmu menjadi bagian teoritis dan praktis.
b. Pembagian pengetahuan menjadi pengetahuan yang dihadirkan (hudhuuri)
dan pengetahuan yang dicapai (hushuuli).
c. Pembagian atas ilmu-ilmu religius (al-‘uluum asy-Syar’iyah) dan
intelektual (‘aqliyah)
d. Pembagian ilmu menjadi fardh ‘ain (wajib atas setiap individu) dan fardh
kifayah (wajib atas umat)33
Al-Ghazali mendefinisikan ilmu-ilmu religius (al-ulum al-Syar’iyah),
sebagai “ilmu-ilmu yang diperoleh para nabi-nabi dan tidak hadir pada mereka
32
Osman Bakar, Hirarki Ilmu, hal. 145-148 33
Osman Bakar, Hirarki Ilmu, hal. 231
19
melalui akal, seperti aritmatika, atau melalui percobaan, seperti pengobatan
(kedokteran), atau dengan mendengar, seperti bahasa. Al-Ghazali menggunakan
istilah ilmu-ilmu religius sebagai sinonim ilmu-ilmu yang ditransmisikan.
Klasifikasi ilmu-ilmu religius terpuji menjadi empat, memasukkan buhkan hanya
ilmu-ilmu kebahasaan, tetapi juga semua ilmu yang secara tradisional
diidentifikasi dengan kategori pengetahuan yang ditransmisikan. Tetapi, dia
menjelaskan bahwa ilmu kebahasaan baru dapat dimasukkan ke dalam kategori itu
sepanjang ia merupakan salah satu pengantar (muqaddimat) dari ilmu-ilmu
religius.
Sedangkan yang dimaksud dengan ilmu-ilmu intelektual (al-ulum al-
‘aqliyah) tidak lain berbagai ilmu yang dicapai atau diperoleh melalui intelek
manusia semata. Adapun pembagiannya sebagai berikut:
a. Ilmu-ilmu religius dibagi menjadi dua: Ilmu tentang prinsip-prinsip dasar
(al-Ushul), dan Ilmu tentang cabang-cabang (furu’) atau prinsip-prinsip
turunan.
Dalam kategori ilmu ushul adalah: Pertama, Ilmu tentang keesaan ilahi
(ilm al-tawhid). Kedua, Ilmu tentang kenabian-Ilmu ini juga berkenaan
dengan ihwal para sahabat serta penerus religius dan spiritualnya. Ketiga,
Ilmu tentang akhirat atau eskatologi. Keempat, Ilmu tentang sumber
pengetahuan religius. Ada dua sumber primer atau dasar, yaitu Al-Qur‟an
dan Sunnah (tradisi-tradisi Nabi). Dua lainnya adalah sumber sekunder;
consensus (ijma’) dan tradisi para Sahabat (atsar al-sahabah).
Ilmu tentang sumber pengetahuan religius terbagi menjadi dua kategori
(a) Ilmu pengantar atau ilmu-ilmu alat (muqaddimah), antara lain ilmu
tulis-menulis dan berbagai cabang ilmu kebahasaan.
(b) Ilmu-ilmu pelengkap (mutammimat) yang terdiri dari;
(1) Ilmu-ilmu Qur‟an termasuk, di dalamnya ilmu tafsir
(interpretasi)
(2) Ilmu-ilmu tentang tradisi nabi seperti ilmu penukilan
(periwayatan hadits)
(3) Ilmu-ilmu tentang pokok-pokok yurisprudensi (ushul al-Fiqh)
20
(4) Biografi yang berhubungan dengan kehidupan para Nabi,
sahabat, dan orang-orang terkenal.
Dalam kategori ilmu tentang cabang-cabang (furu’) atau prinsip-prinsip
turunan adalah:
1. Ilmu tentang kewajiban manusia kepada Tuhan. Ini adalah ilmu
tentang ritus-ritus religius dan pengabdian (ibadah).
2. Ilmu tentang kewajiban manusia kepada masyarakat. Ilmu-ilmu ini
terdiri dari:
(a) Ilmu tentang transaksi. Ilmu ini terutama membentuk transaksi-
transaksi bisnis dan keuangan. Jenis-jenis lain transaksi termasuk
di antaranya qishash (hukum balas-dendam).
(b) Ilmu tentang kewajiban kontraktual. Ilmu ini berhubungan
terutama dengan hukum keluarga.
3. Ilmu tentang kewajiban manusia kepada jiwanya sendiri. Ilmu ini
membahas kualitas-kualitas moral (ilm ‘al-akhlaq)
b. Adapun ilmu-ilmu intelektual, pembagiannya adalah sebagai berikut:
1. Matematika: Artimatika, Geometri, Astronomi dan astrologi, dan
Musik.
2. Logika
3. Fisika atau Ilmu Alam: Kedokteran, Meteorologi, Mineraologi, dan
Kimia
4. Ilmu-ilmu di luar wujud alam atau metafisika:
(a) Ontologi
(b) Pengetahuan tentang esensi, sifat, dan aktifitas ilahi
(c) Pengetahuan tentang substansi sederhana, yaitu intelegensi-
intelegensi dan substansi-substansi malakut (‘angelic)
(d) Pengetahuan tentang dunia halus
(e) Ilmu tentang kenabian dan fenomena kewalian ilmu tentang mimpi
21
(f) Teurigi (nairanjiyaaat). Ilmu ini menggunakan kekuatan-kekuatan
bumi untuk menghasilkan efek tampak seperti supernatural.34
Dari pembagian yang diberikan oleh Al-Ghazali, kiranya dapat difahami
bahwa klasifikasi yang dibangun berdasarkan atas pemahamannya bagi para
pencali ilmu. Dalam persepsinya para pencari ilmu dibagi menjadi empat yaitu
Teolog (mutakallimun), yaitu orang-orang yang mengaku diri mempunayi
spekulasi intelektual dan penalaran bebas. Filosof (Falasifah), yaitu orang-orang
yang mengklaim diri sebagai “ahli logika dan demonstrasi apodeiktik”.
Ta‟limiyah (al-Bathiniyah), yaitu orang-orang yang mengklaim diri sebagai
pemilik satu-satunya al-ta’lim dan penerima hak istimewa pengetahuan yang
diperoleh dari Imam yang tanpa dosa. Dan Sufi (al-Shufah), yaitu orang-orang
yang mengklaim bahwa hanya mereka sajalah yang dapat turut serta dalam
kehadiran Ilahi, dan sebagai orang-orang yang mempunyai visi mistik
(Musyahadah) serta pencerahan (mukasyafah).
Al-Syirazi
Al-Syirazi menyajikan klasifikasi ilmu sebagai berikut:
A. Ilmu-ilmu filosofis (uluum hikmy)
Ilmu-ilmu ini dibagi menjadi ilmu teoretis (nazhariy), yaitu berdasarkan
atas eksistensi yang keberadaannya tidak bergantung pada kehendak manusia.
Sedangkan praktis („amaliy), yaitu yang eksistensi keberadaanya bergantung pada
kehendak manusia.
(1) Ilmu-ilmu filosofis teoretis terdiri dari; Metafisika (Mayor: Ilmu Ilahi
dan Filsafat Pertama. Minor: Ilmu tentang kenabian atau nubuwwah,
Ilmu tentang otoritas religius atau imamah, dan eskatologi),
Matematika (Mayor: Geometri, Aritmetika, Astronomi, dan Musik.
Minor; Optika, Aljabar, Ilmu tentang berat, Pengukuran tanah, Ilmu
hitung, Teknik Mesin, Ilmu tentang neraca timbangan, Ilmu tentang
tabel dan almanac astronomis, dan ilmu tentang irigasi/pengairan).
Filsafat alam / Ilmu Alam (Mayor: Ilmu tentang hal-hal alami yang
34
Osman Bakar, Hirarki Ilmu, hal. 231-237
22
didengar, Sifat benda-benda sederhana dan senyawa, Penciptaan dan
penghancuran benda-benda, Meteorologi, Mineralogi, Botani, Zoologi,
dan Psikologi. Minor: Kedokteran, Astrologi yudisial atau horoskop,
Pertanian, Fisiognomi, Oneiromancy, Sihir alami atau ilmu tentang
tenung, Kimia, dan Theurigi). Dan Logika (dalam ilmu logika, Syirazi
mengikuti pembagian logika paripatetik muslim tradisional menjadi
semblan buku Organon karya Aristoteles).
(2) Ilmu-ilmu filosofis praktis terdiri dari; Etika, Ekonomi, dan Politik.
Pembagian ini didasari atas tiga tipe tindakan manusia yaitu: (1)
Perbuatan individual, (2) Perbuatan kolektif pada level atau keluarga,
dan (3) Perbuatan kolektif pada level kota atau negara.
B. Ilmu-ilmu nonfilosofis (uluum ghair hikmiy) atau Religius
Menurut Qutb al-Din, ilmu religius meliputi antara lain ilmu-ilmu (1)
naqli, (2) ‘aqli (intelektual) atau (3) naqli sekaligus „aqli. Yang dimaksud dengan
ilmu naqli adalah ilmu-ilmu yang hanya dapat dibangun dengan bukti-bukti yang
didengar atau dinukilkan dari otoritas-otoritas yang relevan. Sedangkan ilmu aqli
adalah ilmu-ilmu yang dapat ditetapkan dengan intelek manusia, tidak jadi maslah
apakah ada bukti naqli nya atau tidak.
Ilmu-ilmu ini diistilahkan sebagai ilmu-ilmu religius (diniy) jika
didasarkan atas, atau termasuk dalam, ajaran-ajaran Syari’ah (hukum wahyu). Jika
sebaliknya maka disebut ilmu-ilmu non-religius (ghair diniy).
Ilmu-ilmu religius dapat diklasifikasikan menurut dua cara yang berbeda;
(1) Klasifikasi dalam ilmu-ilmu naqlydan ilmu-ilmu intelektual („aqliy)
(2) Klasifikasi dalam ilmu tentang pokok-pokok atau ushul (Pengetahuan
tentan Esensi unik Tuhan, Pengetahuan tentang Sifat-sifat ilahi,
Pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan, dan Pengetahuan
tentang kenabian dan pesan Ilahi serta kebijaksannannya yang terkait
dengannya). Dan ilmu tentang cabang-cabang atau furu’ (Ilmu yang
dianggap sebagai tujuan : Ilmu tentang Kitab yaitu Al-Qur‟an, Ilmu
tentang Hadits, Ilmu tentang prinsip-prinsip yurisprudensi, dan
23
Yurisprudensi. Ilmu tentang Kesusastraan atau literature; Lafal
idiomatic, Komposisi kata, Etimologi, ilmu I’rab, semantic, Kritik
sastra, Ilmu persajakan, ‘ilmi qawafi, menulis huruf, menulis puisi,
Kaligrafi, Wacana).35
Konsep kunci dalam klasifikasi Quthb Al-Din adalah hikmat (filosofi atau
filsafat). Perbedaan antara bentuk hikmat dan bentuk bukan hikmat pengetahuan
merupakan basis mendasar klasifikasinya.
Dari pembagian klasifikasi tersebut, dapat difahami bahwa Qutb al-Din al-
Syirozi mengklasifikasikan berdasarkan pada makna hikmat yang dalam
pemahamannya tentang hikmat dia mengikuti tradisi ahl ma’rifah (arti harfiah;
orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang benar). Tentang kolompok ini,
Osman Bakar berpendapat yang dimaksud adalah para filosof. Dimana
kecenderungan gagasan-gagasan filosofis Quthb al-Din adalah mazhab filosofis
paripatetik Ibn Sina dan Isyarat Suhrawardi.
Ibnu Khaldun
Ibnu Khaldun membagi ilmu pengetahuan yang dipelajari manusia dalam
dua bagian Pertama, Aqli yakni, ilmu alami bagi manusia yang dapat diperoleh
dengan akal dan pikirannya. Kedua, Naqli, yakni ilmu yang diperoleh dari orang
yang mengajarkannya. Dalam cakupan ilmu Aqliadalah ilmu-ilmu hikmah dan
filsafat, sedangkan dalam cakupan ilmu Naqli adalah ilmu-ilmu yang diajarkan
atau ditransformasikan.36
Ilmu Naqli bersumber pada Al-Qur‟an, Hadits, Ijma‟, dan Qiyas. Yang
termasuk dalam ilmu naqli adalah ilmu tafsir (ilmu tafsir Naqli dan Ilmu tafsir
Aqli), ilmu Qira‟at (termasuk ilmu tulis atau gambar huruf), Ilmu-ilmu Hadits
(berkembang di dalamnya ilmu musthalah hadits), Ilmu Ushul Fiqh, Ilmu Fiqh,
Ilmu Faraidh/Mawarits, Ilmu Kalam, Ilmu Tasawuf, Ilmu Tafsir Mimpi.
Ilmu-ilmu Aqli atau ilmu-ilmu rasional atau dinamakan ilmu filsafat dan
ilmu hikmah, mencakup empat ilmu:
35
Osman Bakar, Hirarki Ilmu, hal. 279-289 36
Ibnu Khaldun, Muqaddimah, alih bahasa. Masturi Irham, dkk. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar,
2012), hal. 804
24
a. Ilmu Logika
b. Ilmu Alam: Ilmu Kedokteran, Pertanian, Psikologi, Fisika, Kimia
c. Ilmu ilahy atau ilmu ketuhanan/Teologi (Metafisika)
d. Ilmu yang mengamati tentang ukuran-ukuran (Bilangan): Teknik; ilmu
pertanahan, Optik, Aritmatika: Ilmu berhitung, Al-Jabar, Ilmu
Perbandingan, Mu‟amalah, Ilmu Faraidh, Musik, dan Astronomi; Ilmu
teknik tabel-tabel astronomi, ilmu hukum perbintangan.
Selain daripada dua ilmu tersebut, terdapat ilmu alat (ilmu lisan) untuk
memahami ilmu-ilmu agama yaitu ilmu bahasa, dalam ilmu bahasa terdapat Ilmu
Nahwu, Ilmu Lughah, Ilmu Bayan, dan Ilmu Adab
Paradigma Integrasi Ilmu
Imam Suprayogo menyebutkan bahwa klasifikasi ilmu pengetahuan saat
ini dalam tiga golongan yaitu ilmu-ilmu alam (natural science), ilmu sosial (social
science), dan ilmu-ilmu humaniora (humanities). 37
Ilmu-ilmu alam yang bersifat
murni (pure science) adalah Ilmu Fisika, Ilmu Kimia, Ilmu Biologi, dan sementara
orang memasukkan Matematika. Ilmu sosial yang masuk kategori ilmu murni
(pure science) adalah Ilmu Sosiologi, Ilmu Psikologi, Ilmu Antropologi, dan Ilmu
Sejarah. Sedangkan Ilmu humaniora yang termasuk kategori ilmu murni (pure
science) adalah ilmu bahasa, ilmu filsafat, ilmu sastra, dan seni. Dari ilmu murni
(pure science) tersebut berkembang menjadi ilmu-ilmu terapan (applied science)
yang terus berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
Lalu kemudian umat Islam memiliki cara pandang yang berbeda mengenai
ilmu-ilmu tersebut, yaitu dengan melandasinya berdasarkan Al-Qur‟an dan
Hadits. Al-Qur‟an dan Hadits dalam pengembangan ilmu diposisikan sebagai
sumber ayat-ayat qawliyah sedangkan hasil observasi, eksperimen dan penalaran
logis diposisikan sebagai sumber ayat-ayat kawniyah. Dengan posisinya seperti ini
37
Imam Suprayogo, Paradigma Pengembangan Keilmuan Islam; Perspektif UIN Malang,
(Malang: UIN Malang Press, 2006), hal. 22
25
maka berbagai cabang ilmu pengetahuan selalu dapat dicari sumbernya dari Al-
Qur‟an dan hadits.38
Dengan gambaran tersebut yaitu pembagian ilmu pengetahuan dan
pembagian al-Qur‟an sebagai ayat qawliyah dan ayat kawniyah adalah merupakan
satu alternative dalam membangun keilmuan yang bersifat integrative. Sehingga
tidak terjadi pemisahan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu umum.
Sejalan dengan hal tersebut adalah diungkapkan oleh Azhar Arsyad, yang
mengutip pendapat dalam Konferensi Pendidikan Islam Sedunia I di Makkah pada
1977. ilmu pengetahuan menjadi dua yaitu ilmu Naqli dan ‘Aqli, sedangkan dalam
ilmu ‘Aqli juga dibagi menjadi sains-sains alam (natural science), dan sains
kemanusiaan (social science and humanities).39
Dalam pendapatnya juga disebutkan bahwa sains adalah sejumlah konsep
dan binaan hipotesis (hypothetical construct) yang terwujud sebagai hasil dari
pada proses pengamatan dan eksperimen yang pada gilirannya membawa kepada
lebih banyak pengamatan dan eksperimen.40
Dari hal tersebut dimaknai sains
memiliki dua unsur utama yaitu kandungan sains tersebut dan proses yang
membawa kepada upaya menemukan fakta dan konsep yang membentuk
kandungan itu.
Integrasi dan interkoneksitas yang dikonsepsikan Azhar Arsyad adalah
gambaran Sel Cemara. Dengan akar adalah Al-Qur‟an dan Sunnah, kemudian
batang (1) Ilmu alat untuk memahami al-Qur‟an utamanya bahasa Arab, (2) Alat
untuk mendapat ilmu yaitu Panca indra, akal, dan intuisi (ilham dan wahyu), dan
(3) Methodology and Approach.41
Dan pada buahnya muncul berbagai ilmu
pengetahuan. Sel cemara itu didahului dengan aktifitas fisik dan emosi yang
mengorbit pada Spiritual Quoition (SQ). Di dalamnya merupakan perpaduan
antara IQ, EQ, dan SQ.
38
Imam Suprayogo, Paradigma Pengembangan Keilmuan Islam; hal. 30 39
Azhar Arsyad, Buah Cemara Integrasi dan Interkoneksitas Sains dan Ilmu Agama, dalam Jurnal
Hunafa Vol. 8. No. 1 Juni 2011, hal. 3 40
Azhar Arsyad, Universitas Islam; Integrasi dan Interkoneksitas Sains dan Ilmu Agama Menuju
Peradaban Islam Universal, dalam Jurnal Tsaqafah Vol. 2, No. 2, 2006/1427, hal. 162 41
Azhar Arsyad, Buah Cemara Integrasi dan Interkoneksitas Sains dan Ilmu Agama, hal. 12
26
4. Tokoh-Tokoh Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dalam Islam
a. Al-Kindi
Abu Yusuf Ya‟qub ibnu Ishaq Al-Kindi (801/873), yang dikenal dengan
sebutan Al-Kindi. Adalah seorang filosof Muslim pertama dan ilmuwan dalam
bidang filsafat, matematika, logika, sampai kepada music, dan ilmu kedokteran.
Minat besarnya pada kajian filsafat menjadikan dirinya sebagai tokoh pendiri
filsafat paripatetik Islam. Dalam pandangan Al-Kindi, Filsafat adalah pengetahuan
tentang yang benar. Agama dan Filsafat tidak saling bertentangan, karena
keduanya bertujuan mencari yang benar. Agama berdasar wahyu, dan filsafat
berdasar akal. Yang Benar Pertama adalah Tuhan, dan filsafat tertinggi adlaah
filsafat ketuhanan.
b. Al- Farabi
Abu Nasr Al-Farabi (870-900), orang barat menyebutnya Al-Farabius.
Adalah tokoh Islam yang pertama dalam bidang logika sehingga sebutannya
adalah al-Mu’allim al-Thani, karena komentarnya atas filsafat Aristoteles. Al-
Farabi mengembangkan dan mempelajari ilmu fiskia, matematika, etika, filsafat,
politik, dan lain sebagainya.
Diantara karyanya adalah al-Madinah al-Fadhilah yang menjadi rujukan
akademisi dan praktisi politik di kemudian hari. Dalam hal filsafat ketuhanan, al-
Farabi menemukan teori emanasi. Selain daripada itu al-Farabi juga membuat
hirarki ilmu pengetahuan sebagaimana dijelaskan di atas.
c. Al-Razi
Muhammad Ibnu Zakaria Al-Razi (865-965 M/ 251-313 H) atau di Barat
dikenal dengan sebutan Razes. Dia adalah seorang dokter klinis terbesar pada
zamannya. Bidang keahliannya, adalah Alchemiyang sekarang kita kenal dengan
ilmu kimia, dan ilmu kedokteran.
d. Jabir Bin Hayyan
27
Jabir Ibnu Hayyan (721-815 M/ 103-200 H) adalah seorang tokoh Islam
pertama yang mempelajari dan mengembangkan Alchemi di dunia Islam. Ilmu ini
kemudian berkembang dan kita kenal sekarang sebagai ilmu kimia, karya
utamanya adalah Miah wa Itsnaasyar Kitab dan Sab’ata Asyar Kitab. Bidang
keahliannya yang lain adalah bidang logika, filsafat, kedokteran, fisika, mekanika.
e. Ibnu Haitham
Abu Ali Al-Hasan Ibnu Haitham (965-1039), dikenal dengan nama Latin
Al-Hazen. Adalah seorang ahli fisika yang ternama dan seorang ahli fisika Islam
yang pertama. Kecuali ilmu fisika ia juga mengembangkan ilmu-ilmu lain sepertai
ilmu matematika, astronomi, ilmu jiwa, dan ilmu kedokteran. Karyanya yang
paling utama adalah di bidang optic.
f. Ibnu Sina
Abu Ali Al-Husein Ibnu Sina (980-1037 M/ 370-428 H), yang dilatinkan
dengan nama Avicenna. Dia adalah seorang ilmuwan dan filosof yang besar pada
waktu itu, hingga kepadanya diberikan julukan Syeikh al-Rais. Bidang
keahliannya adalah ilmu fisika, geologi, ilmu kedokteran, mineralogy, dan lain
sebagainya.
Ibnu Sina menyempurnakan teori emanasi al-Farabi. Dan memperdalam
dan menambah secara lebih detail teori spekulatif al-Farabi dalam logika,
epistemology, dan metafisika
g. Al-Khawarizmi
Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi (w. 863 M/ 249 H), yang sangat
terkenal dengan bidang matematika, di antara karyanya adalah al-Jabr wa al-
Muqabalah (Aljabar).
h. Al-Ghazali
Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali (1059-1111 M / 450-
505 H), dikenal dengan al-Ghazali. Bidang yang dikuasai mencakup berbagai
28
ilmu pengetahuan di antaranya filsafat, kalam, tasawuf. Dan menulis banyak karya
yang terkenal di antaranya adalah Maqaashid al-Falasifah, Tahafut al-Falasifah,
Ihya Ulumiddin.
i. Ibnu Rusyd
Abu al Walid Muhammad Ibnu Rusyd (1126-1198) yang dikenal di Barat
dengan sebutan Averroes. Tokoh ini dalam pandangan Barat adalah seorang tokoh
yang besar sehubungan dengan aliran rasionalisme yang disamping astronomi,
filsafat, dan lain-lainnya. Karyanya yang terkenal adalah kritik atas al-Ghazali
dengan kitab Tahafut at-Tahaafut.
j. Al-Syirozi
Quthb al-Din Mahmud ibn Dhia al-Din Mas‟ud al-Syirozi (1236-1311 M/
634-710 H), dikenal dengan sebutan Al-Syirozi. Al-Syirozi mempunyai minat
universal hampir pada semua cabang ilmu dan seni di samping filsafat dan teologi.
Karya-karyanya banyak di berbagai bidang ilmu pengetahuan tentang kedokteran,
geometri, optika, astronomi, geografi, ilmu bahasa, filsafat, dan ilmu-ilmu religius
termasuk komentar-komentar atas al-Qur‟an. Karya utamanya dalam pembagian
ilmu adalah kitab Durrat al-Taj, dalam bidang astronomi kitab Nihayat al-Idrak fi
dirayat al-Aflak dan Al-Tuhfat al-Syahiyah fi l-haiah.
k. Ibnu Khaldun
Abdullah Abd al-Rahman Abu Zayd Ibn Muhammad Ibn Khaldun (1332-
1406 M/ 732-808 H), dikenal dengan sebutan Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah
sejarawan dan bapak sosiologi modern. Bidang kajiannya adalah Politik,
Sosiologi, Ekonomi, Sejarah, Tasawuf, dan berbagai ilmu pengetahuan yang lain.
Karyanya yang monumental adalah Muqaddimah.
C. Kesimpulan
Dari pemaparan pemakalah di atas kiranya dapat diambil beberapa kesimpulan
berikut:
29
a. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam
Perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam seiring bersamaan dengan
pemahaman dan pemaknaan Al-Qur‟an dan Sunnah. Selain daripada itu,
Pertemuan budaya dan ilmu dengan peradaban lain, para cendekiawan muslim
turut berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, pun demikian tidak
melepaskan dari Al-Qur‟an dan Sunnah.
b. Hakikat ilmu pengetahuan dalam Islam
Ilmu pengetahuan dalam Islam menyangkut dua hal yang tidak terpisahkan
satu sama lain, yaitu ilmu sebagai objek dan ilmu sebagai proses. Sehingga ilmu
yang didapatkan tidak menjadi bebas nilai, karena di sana terdapat proses yang
juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari ilmu pengetahuan.
c. Pembagian ilmu pengetahuan dalam Islam
Pada hakikatnya tidak terdapat dikotomi ilmu pengetahuan dalam Islam.
Karena pada dasarnya Al-Qur‟an dalam kalam Tuhan mengenai alam semesta dan
isinya, sedangkan seisi alam semesta adalah ciptaan-Nya yang menjadi objek
kajian ilmu pengetahuan. Namun pembagian yang dilakukan al-Ghazali sebagai
fardhu ‘ain dan fardhu kifayah adalah merupakan suatu ikhtiar untuk memahami
bahwa sebaik apapun ilmu pengetahuan pada hakikatnya adalah untuk
mempersiapkan kita menuju akhirat. Maka selain menentukan dengan fardhu ‘ain
dan fardhu kifayah, al-Ghazali memberikan tiga tingkatan dalam mendalami ilmu-
ilmu tersebut.
d. Tokoh-tokoh perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam
Ada banyak tokoh-tokoh ilmu pengetahuan yang muncul dalam Dinasti
Bani Umayyah, dan lebih banyak lagi pada Dinasti Bani Abbasiyah. Dari semua
tokoh tersebut, pada umumnya adalah selain menguasai berbagai ilmu
pengetahuan seperti filsafat, kimia, kedokteran, sastra, seni, mereka juga
mendalami ilmu agama. Model penguasaan ilmu pengetahuan agama dan ilmu
pengetahuan umum dalam diri para ulama dan ilmuwan pada masa kejayaan
Islam, menjadi motivasi bagi para cendekiawan muslim saat ini untuk
merumuskan suatu model integrasi ilmu pengetahuan.
30
Daftar Rujukan
Al-Syaibany, Omar Mohammad Al-Toumy, Falsafah at-Tarbiyah al-Islamiyah,
alih bahasa Hasan Langgulung, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
Amir, Syamsuddin, Mendefinisiak dan Memetakan Ilmu, dalam Adian Husaini,
et.al. Filsafat Ilmu: Perspektif Barat dan Islam, Depok: Gema Insani
Press, 2013.
Barbour, Ian G. Juru Bicara Tuhan: Antara Sains dan Agama, Bandung : Mizan,
2002.
Ghulsyani, Mahdi, Filsafat Sains Menurut Al-Qur’an, alih bahasa Agus Efendi,
Bandung: Mizan, 1998.
Husaini, Adian, et.al. Filsafat Ilmu: Perspektif Barat dan Islam, Depok: Gema
Insani Press, 2013.
Ibnu Khaldun, Muqaddimah, alih bahasa. Masturi Irham, dkk. Jakarta: Pustaka al-
Kautsar, 2012
Kania, Dinar Dewi, Objek Ilmu dan Sumber-Sumber Ilmu, dalam Adian Husaini,
et.al. Filsafat Ilmu: Perspektif Barat dan Islam, Depok: Gema Insani
Press, 2013.
Langgulung, Hasan, Pendidikan Islam Menghadapi Abad ke 21, Jakarta: Radar
Jaya, 1988.
_____, Asas-Asas Pendidikan Islam, Jakarta: Penerbit Al-Husna, 1987.
Mahzar, Armahedi, Revolusi Integralisme Islam: Merumuskan Paradigma Sanis
dan Teknologi Islami, Bandung: Mizan, 2004.
Nasution, Harun Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran, Bandung: Mizan,
1998.
Ramayulis dan Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam; Telaah Sistemis
Pendidikian dan Pemikiran Para Tokohnya, Bandung: Kalam Mulia,
2009.
Shihab, Quraish, Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan
Umat, Bandung: Mizan, 2012.
Sunanto, Musyrifah, Sejarah IslamKlasik; Perkembangan Ilmu Pengetahuan
Islam, Jakarta: Kencana, 2004.
31
Suprayogo, Imam, Paradigma Pengembangan Keilmuan Islam; Perspektif UIN
Malang, Malang: UIN Malang Press, 2006.
_____, Universitas Islam Unggul: Refleksi Pemikiran Pengembangan
Kelembagaan dan Reformulasi Paradigma Keilmuan Islam, Malang: UIN
Malang Press, 2009.
Wan Daud, Wan Mohd Nor, The Educational Philosophy and Practice of Syed
M. Naquib Al-Attas, alih bahasa Hamid Fahmi, dkk. Bandung: Mizan,
1998.
Jurnal
Arsyad, Azhar, Buah Cemara Integrasi dan Interkoneksitas Sains dan Ilmu
Agama, dalam Jurnal Hunafa Vol. 8. No. 1 Juni 2011, hal. 3
_____, Universitas Islam; Integrasi dan Interkoneksitas Sains dan Ilmu Agama
Menuju Peradaban Islam Universal, dalam Jurnal Tsaqafah Vol. 2, No. 2,
2006/1427, hal. 162
Rasmianto, Relasi Agama dan Sains dalam Studi Islam di PTAI, dalam Ulul
Albab Jurnal Studi Islam, Vol.9. No. 1. 2008, hal. 18
Shobahussurur, Lembaga Pendidikan Dalam Khazanah Islam Klasik; Telaah atas
Proses Sejarah dan Transmisi Ilmu Pengetahuan, Vol. 2, No. 2,
2006/1427
Suprayogo, Imam. Perjuangan Mewujudkan Universitas Islam (Pengalaman UN
Malang), Jurnal Tsaqafah Vol. 2, No. 2, 2006/1427