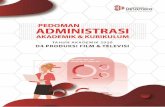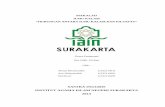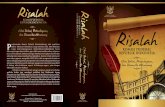Dinamika Ilmu 2012 Vol 12 No 1
-
Upload
iain-samarinda -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Dinamika Ilmu 2012 Vol 12 No 1
PERAN SUPERVISI DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN ISLAM
Siti Muriah
Abstract ; Comparing to other states, quality of education in Indonesia including Islamic education has not shown significant progress. It can be verified from the report of PERC, World Bank, and data from UNDP. It is a regret to find the decrease of our education quality. It occurs because supervision of education is done in conventional manner, rigid, and formality limited. Moreover, it may also because instructional activities have not been optimal yet and management of education institution which is less professional. In order to solve the problem, some solutions are offered. One of them is that the implementation of supervision has to be done optimally, procedurally, and professionally. In this case, supervision takes its role as, (1) academic supervision: teacher partner, innovator, and pioneer, instructional and education consultant, teachers counselor, and motivator, (2) managerial supervision: concept drafter, programmer, composer, reporter, and builder. Furthermore, manager (headmaster) has to be able to concentrate and supervise the effort to have a good input through very good process to produce excellent output: moderate input through excellent process produces very good output; and the lower input through a very excellent process resulting better output. Keywords : Peran Supervisi, Mutu, Pendidikan Islam A. PENDAHULUAN
Tidak dapat dipungkiri bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan, apalagi jika dibandingkan dengan mutu pendidikan di Negara lain. Hasil survey Political and Ekonomic Risk Consultancy (PERC) yang dilakukan pada tahun 2000 tentang mutu pendidikan di kawasan Asia, menempatkan Indonesia pada rangking 12 satu tingkat dibawah Vietnam.
Disamping itu, menurut laporan Bank Dunia mengenai mutu peserta didik yang dihasilkan lembaga pendidikan di Indonesia bahwa ketrampilan membaca siswa kelas IV SD berada pada tingkat terendah di Asia Timur setelah Philipina, Thailand, Singapura dan Hongkong. Berdasarkan penelitian, rata-rata nilai tes siswa SD kelas VI untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, Matematika dan IPA dari tahun ke tahun semakin menurun. Anak-anak di Indonesia hanya dapat menguasai 30 % materi bacaan, bahkan mereka sulit sekali menjawab soal-soal berbentuk uraian yang memerlukan penalaran. Data tersebut dipertegas dengan indikator pembangunan manusia yang salah satu ukurannya adalah tingkat pendidikan yang dikembangkan UNDP (United Nations Development Programme), data terbaru menempatkan Indonesia berada
Penulis adalah dosen tetap Jurusan Tarbiyah, Guru Besar Pada STAIN Samarinda
Kalimantan Timur
2
pada posisi sekitar 40 % terbawah diantara 174 negara yang dinilai. Rasio untuk pendidikan dasar mencapai 97 % dan rasio untuk pendidikan menengah 62 % dan bahkan data terakhir menempatkan Indonesia pada urutan ke-108 dari 177 negara yang diikutkan (HDI, 2006).
Selain itu, mutu perguruan tinggi nasional di Indonesia juga sangat rendah yang menempati rangking papan bawah dibandingkan dengan perguruan tinggi di kawasan Asia. Hasil riset mingguan Asiaweek (www.cnn.com/AsiaNow/Asiaweek) pada tahun 2000 menempatkan Universitas Indonesia Jakarta pada urutan 61, Universitas Gajah Mada Yogyakarta 68, Universitas Diponegoro Semarang 73, dan Universitas Airlangga Surabaya 75 dari 77 universitas multidisiplin di Asia, Australia, dan Selandia Baru. Sedangkan untuk kategori Science dan Technology Schools, Institut Teknologi Bandung menduduki peringkat 21 dari 39 universitas.1 Dalam hal ini juga tidak terlepas mutu lembaga pendidikan Islam diberbagai jenjang pendidikan mengalami penurunan.
Pada sisi lain, krisis multidimensional yang dialami bangsa Indonesia, tidak hanya berdampak pada bidang ekonomi, politik dan sosial kemasyarakatan, namun juga telah merambah pada bidang mental spiritual, yakni merosotnya akhlak dan budi pekerti pada sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal ini menuntut semua pihak untuk berpikir cerdas dan serius dalam hal bagaimana meningkatkan moralitas bangsa dan mengembalikan citra bangsa Indonesia, khususnya pada generasi muda dan anak-anak Indonesia sebagai aset yang sangat fundamental dalam setiap aktivitas pemberdayaan manusia sebagaimana yang menjadi hakikat dan tujuan pendidikan itu sendiri.
Atas dasar berbagai keprihatinan terhadap kondisi dunia pendidikan kita, utamanya terhadap supervisi, pengelolaan pendidikan yang sebagian besar masih konvensional sangat mempengaruhi mutu pendidikan, yaitu lembaga pendidikan menghasilkan pebelajar dengan hasil belajar yang baik, hasil belajar yang biasa dan hasil belajar tergolong kurang baik. Kalau kita telaah keberadaan lembaga pendidikan di Indonesia baik dibawah Dinas Pendidikan maupun Mapenda Kemenag mengalami penurunan mutu disebabkan beberapa hal, diantaranya adalah: pertama supervisi pendidikan tidak dilaksanakan secara profesional, terkendala pemahaman dan pelaksanaan supervisi yang masih kaku dan sebatas formalitas, yaitu masih ada jarak antara supervisor dengan guru. Kedua, belum optimalnya kegiatan pembelajaran karena terkendala keterbatasan sarana dan prasarana terutama di lembaga pendidikan yang terletak di daerah, khususnya daerah terpencil. Ketiga, Keberadaan data nasional yang diperoleh dari hasil Ujian Nasional, tidak sepenuhnya di dapat melalui proses ujian nasional yang penuh kejujuran. Hasilnya, walaupun secara kuantitatif menunjukkan adanya
1 Abdul Hadis, Nurhayati, Manajemen Mutu Pendidikan, (Bandung: ALFABETA, 2010), hal. 2
3
peningkatan yang signifikan pada kenaikan nilai hasil pembelajaran, namun secara kualitatif, proses pelaksanaannya banyak dijumpai praktik-praktik kecurangan sehingga banyak menimbulkan keprihatinan bagi para insan pendidikan kita. Keempat, sudah menjadi rahasia umum bahwa masih banyak birokrat dibidang pendidikan yang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sejak era Orde Baru sampai era reformasi berjalan lebih satu dasawarsa, fenomena ini masih saja selalu dalam bentuk yang serupa tetapi tidak sama,2 bahkan sudah mendarah daging dan susah untuk diberantas. Inilah kondisi yang memprihatinkan dunia pendidikan kita. Oleh karena itu, sudah saatnya kita sebagai pemikir dan praktisi pendidikan bekerja keras untuk merubah kondisi yang demikian menjadi kondisi yang lebih baik.
Berangkat dari fenomena dan kenyataan diatas, sudah seharusnya kita sebagai praktisi pendidikan, berjuang keras memerangi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan kita. Kita harus melakukan terobosan baru diantaranya melakukan supervisi yang profesional dalam lembaga pendidikan agar mutu pendidikan dapat kita raih sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dari sinilah,akan dihadirkan sebuah tulisan ini dalam bentuk makalah dengan tema “Peran Supervisi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam.” B. PENGERTIAN SUPERVISI PENDIDIKAN
Kata supervisi berasal dari bahasa Inggris “supervision” yang terdiri dari dua kata “super” dan “vision”. Super berarti atas atau lebih, sedangkan vision berarti melihat atau meninjau. Oleh karena itu, secara etimologi supervisi adalah melihat dan meninjau dari atas atau menilik dan menilai dari atas yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap aktivitas, kreativitas, dan kinerja bawahan.3
Supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif.4
Terdapat beberapa istilah yang hampir sama dengan supervisi, bahkan dalam pelaksanaannya istilah-istilah tersebut sering digunakan secara bergantian. Istilah-istilah tersebut, antara lain, pengawasan, pemeriksaan, dan inspeksi. Pengawasan mengandung arti suatu kegiatan untuk melakukan pengamatan agar pekerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan. Pemeriksaan dimaksudkan untuk melihat bagaimana kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai tujuan. Inspeksi dimaksudkan untuk mengetahui kekurangan-
2Moh. Makin Baharuddin, Manajemen Pendidikan Islam Transformasi Menuju
Sekolah/Madrasah Unggul, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hal. 3 3 E. Mulyasa, E, Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara,
2011), hal. 239 4 M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, Cet. xix, (Bandung:
Rosdakarya, 2009), hal. 76
4
kekurangan atau kesalahan yang perlu diperbaiki dalam suatu pekerjaan. Oleh karena itu, deskripsi istilah-istilah diatas identik dengan supervisi sehingga wajar kalau dalam penggunaannya sering dipertukarkan.
Kalau kita telaah, dalam pemakaiannya secara umum supervisi diberi arti sama dengan direktur, dan manajer. Dalam bahasa umum ini ada kecondongan untuk membatasi pemakaian istilah supervision pada orang-orang yang berada dalam kedudukan yang lebih bawah dalam hirarki manajemen. Istilah-istilah umum bagi kedudukan ini selain dari supervisor adalah foremen dan supertendent, yang dinegara kita disebut “mandor” pengawas, “opsiner”, dan “opseter”. Merekalah yang bertanggung jawab secara langsung dan bertatap muka tentang kegiatan-kegiatan dari hari ke hari sekelompok pegawai bawahan. Fungsi-fungsi mereka meliputi penugasan dan pembagian pekerjaan, pemeriksaan efisiensi dari proses, metode dan tehnik yang digunakan, pengadaan alat perlengkapan yang diperlukan. Seorang supervisor juga sering diberi kekuasaan untuk mengangkat, memberhentikan atau memindahkan pekerja, dan untuk melakukan tindakan-tindakan lain selaku seorang manajer.
Kemudian, konsep supervisi modern dirumuskan oleh Kimball Wiles (1967) sebagai berikut : “Supervision is assistance in the devolepment of a better teaching learning situation”. Supervisi adalah bantuan dalam pengembangan situasi pembelajaran yang lebih baik. Rumusan ini mengisyaratkan bahwa layanan supervisi meliputi keseluruhan situasi belajar mengajar (goal, material, technique, method, teacher, student, an envirovment). Situasi belajar inilah yang seharusnya diperbaiki dan ditingkatkan melalui layanan kegiatan supervisi. Dengan demikian layanan supervisi tersebut mencakup seluruh aspek dari penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran.
Konsep supervisi tidak bisa disamakan dengan inspeksi, inspeksi lebih menekankan kepada kekuasaan dan bersifat otoriter, sedangkan supervisi lebih menekankan kepada persahabatan yang dilandasi oleh pemberian pelayanan dan kerjasama yang lebih baik diantara guru-guru, karena bersifat demokratis. Istilah supervisi pendidikan dapat dijelaskan baik menurut asal usul (etimologi), bentuk perkataannya (morfologi), maupun isi yang terkandung dalam perkataan itu ( semantik). a. Etimologi
Istilah supervisi diambil dalam perkataan bahasa Inggris “ Supervision” artinya pengawasan di bidang pendidikan. Orang yang
melakukan supervisi disebut supervisor. b. Morfologis
Supervisi dapat dijelaskan menurut bentuk perkataannya. Supervisi terdiri dari dua kata. Super berarti atas, lebih. Visi berarti lihat, tilik, awasi. Seorang supervisor memang mempunyai posisi diatas atau mempunyai kedudukan yang lebih dari orang yang disupervisinya.
c. Semantik
5
Pada hakikatnya isi yang terkandung dalam definisi yang rumusanya tentang sesuatu tergantung dari orang yang mendefinisikan. Wiles secara singkat telah merumuskan bahwa supervisi sebagai bantuan pengembangan situasi mengajar belajar agar lebih baik. Adam dan Dickey merumuskan supervisi sebagai pelayanan khususnya menyangkut perbaikan proses belajar mengajar. Sedangkan Depdiknas (1994) merumuskan supervisi sebagai berikut : “ Pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik”.
Dengan demikian, supervisi ditujukan kepada penciptaan atau pengembangan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Untuk itu ada dua hal (aspek) yang perlu diperhatikan. Pertama, Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, yang kedua, Hal-hal yang menunjang kegiatan belajar mengajar
Karena aspek utama adalah guru, maka layanan dan aktivitas kesupervisian harus lebih diarahkan kepada upaya memperbaiki dan meningkatkan kemampuan guru dalam mengelola kegiatan belajar mengajar. Untuk itu guru harus memiliki yakni : 1) kemampuan personal, 2) kemampuan profesional 3) kemampuan sosial.5
Berangkat dari uraian diatas dapat ditarik benang merah, yang dimaksud dengan supervisi pendidikan adalah bimbingan profesional bagi guru-guru. Bimbingan profesional yang dimaksudkan adalah segala usaha yang memberikan kesempatan bagi guru-guru untuk berkembang secara profesional, sehingga mereka lebih maju lagi dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memperbaiki dan meningkatkan proses belajar siswa.
C. PENGERTIAN MUTU PENDIDIKAN ISLAM
Menurut Juran dalam Hadis dan Nurhayati6 mutu produk adalah kecocokan penggunaan produk (fitness for use) untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Kecocokan pengguna produk tersebut didasarkan atas lima ciri utama, yaitu (1) teknologi yaitu kekuatan, (2) psikologis, yaitu citra rasa atau status, (3) waktu, yaitu kehandalan, (4) kontraktual, yaitu ada jaminan, (5) etika, yaitu sopan santun.
Menurut Crosby7 mutu adalah conformance to requirement, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan. Suatu produk memiliki mutu apabila sesuai dengan standar atau kriteria mutu yang telah ditentukan, standar mutu tersebut meliputi bahan baku, proses produksi, dan produk jadi.
5 Depdiknas, Petunjuk Pengelolaan Adminstrasi Sekolah Dasar,( Jakarta: Depdiknas,1997),
hal. 47 6 Abdul Hadis, Nurhayati, Manajemen, hal. 84 7 P.B. Crosby, Quality in Free, (New York: McGraw Hill Book Inc, 1979), hal. 58
6
Menurut Deming 8 mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Perusahaan yang bermutu adalah perusahaan yang menguasai pangsa pasar karena hasil produksinya sesuai dengan kebutuhan konsumen, sehingga menimbulkan kepuasan bagi konsumen. Jika konsumen merasa puas, maka mereka akan setia dalam membeli produk perusahaan tersebut baik berupa barang maupun jasa.
Menurut Feigenbaum 9 mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya (full customer satisfaction). Suatu produk dianggap bermutu apabila dapat memberikan kepuasan sepenuhnya kepada konsumen, yaitu sesuai dengan harapan konsumen atas produk yang dihasilkan oleh perusahaan.
Menurut Garvi dan Davis (1994) dalam Hadis dan Nurhayati 10 mutu adalah suatu kondisi dinamik yang berhubungan dengan produk, tenaga kerja, proses, tugas serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Dengan perubahan mutu produk tersebut, diperlukan peningkatan atau perubahan ketrampilan tenaga kerja, proses produksi, dan tugas, serta perubahan lingkungan perusahaan agar produk dapat memenuhi dan melebihi harapan konsumen.
Dari beberapa pendapat pakar mutu diatas dapat diambil benang merah, bahwa pengertian mutu pendidikan dapat diartikan sebagai gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat.
Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan out put pendidikan.11 Mengenai input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Sesuatu yang dimaksud berupa sumberdaya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. Input sumberdaya meliputi sumberdaya manusia (kepala sekolah/madrasah, guru/ustadz termasuk guru BP, karyawan, dan siswa) dan sumberdaya selebihnya (peralatan, perlengkapan, uang, bahan, dan sebagainya). Input perangkat lunak meliputi struktur organisasi sekolah/madrasah, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana, dan program. Input harapan-harapan berupa visi, misi, tujuan, dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh sekolah/madrasah. Kesiapan input sangat diperlukan agar proses dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, tinggi rendahnya mutu input dapat diukur dari tingkat kesiapan input. Makin tinggi kesiapan input, makin tinggi pula mutu input tersebut.
8 W.E. Deming, Out of Crisis, (Cambridge: Massachussets Institute of Technology,
1982), hal. 176 9 Feigenbaum, Total Quality Control, (New York: McGraw Hill Book Inc, 1986), hal. 7 10 Abdul Hadis, Nurhayati, Manajemen, hal. 86 11 Depdiknas, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, (Buku 1). (Jakarta:
Depdikna, 2001), hal. 5
7
Selanjutnya adalah proses pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut input, sedang sesuatu dari hasil proses disebut output. Dalam pendidikan berskala mikro (tingkat sekolah/madrasah), proses yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar, dan proses monitoring dan evaluasi, dengan catatan bahwa proses belajar mengajar memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibandingkan dengan proses-proses lainnya.
Proses dikatakan bermutu tinggi apabila pengkoordinasian dan penyerasian serta pemaduan input sekolah (guru/ustadz, siswa/santri, kurikulum, uang, peralatan, dan sebagainya) dilakukan secara harmonis, sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan (enjoyable learning), mampu mendorong motivasi dan minat belajar, dan benar-benar mampu memberdayakan peserta didik. Kata memberdayakan mengandung arti bahwa peserta didik/santri tidak sekedar menguasai pengetahuan yang diajarkan oleh gurunya atau ustadznya, akan tetapi pengetahuan tersebut juga telah menjadi muatan nurani peserta didik/santri, dihayati, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang penting lagi peserta didik/santri tersebut mampu belajar cara belajar (mampu mengembangkan dirinya).
Kemudian berikutnya output pendidikan adalah merupakan kinerja sekolah/madrasah. Kinerja sekolah/madrasah adalah prestasi sekolah/madrasah yang dihasilkan dari proses/perilaku sekolah. Kinerja sekolah/madrasah dapat diukur dari kualitasnya, efektivitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya, dan moral kerjanya. Khusus yang berkaitan dengan mutu output sekolah/madrasah, dapat dijelaskan bahwa output sekolah/madrasah dikatakan berkwalitas atau bermutu tinggi jika prestasi sekolah/madrasah, khususnya prestasi siswa/santri, menunjukan pencapaian yang tinggi dalam: (1) prestasi akademik berupa ulangan umum, nilai ujian akhir, karya ilmiah, lomba-lomba akademik; dan (2) prestasi non-akademik, seperti misalnya IMTAQ, kejujuran, kesopanan, olahraga, kesenian, ketrampilan, , dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Mutu sekolah/madrasah dipengaruhi oleh banyak tahapan kegiatan yang saling berhubungan (proses) seperti misalnya supervisi, perencanaan, pelaksanaan.12 Dari uraian diatas dapat dipertegas, bahwa supervisi termasuk bagian terpenting yang berperan dalam peningkatan mutu pendidikan Islam, karena bersentuhan langsung dengan kondisi dilapangan baik yang berhubungan dengan input, proses maupun output pendidikan.
12 E. Mulyasa, Manajemen & Kepemimpinan, hal. 158
8
D. PRINSIP-PRINSIP SUPERVISI PENDIDIKAN ISLAM Secara sederhana prinsip-prinsip supervisi pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Supervisi hendaknya bersifat konstruktif dan kreatif, yaitu pada yang dibimbing dan diawasi harus dapat menimbulkan dorongan untuk bekerja.
b. Supervisi didasarkan atas keadaan dan kenyataan yang sebenar-benarnya (realistis, mudah dilaksanakan).
c. Supervisi harus sederhana dan informal pelaksanaannya. d. Supervisi harus dapat memberikan perasaan aman pada guru-
guru/ustadz dan pegawai-pegawai sekolah/madrasah yang di supervisi. e. Supervisi harus didasarkan atas hubungan profesional, bukan atas dasar
hubungan pribadi f. Supervisi harus selalu memperhitungkan kesanggupan, sikap, dan
mungkin prasangka guru-guru dan pegawai sekolah/madrasah. g. Supervisi tidak bersifat mendesak (otoriter) karena dapat menimbulkan
perasaan gelisah atau bahkan antipati dari guru-guru/ustadz. h. Supervisi tidak boleh didasarkan atas kekuasaan pangkat, kedudukan,
atau kekuasaan pribadi. i. Supervisi tidak bersifat mencari-cari kesalahan dan kekurangan. Ingat
bahwa supervisi berbeda dengan inspeksi! j. Supervisi tidak dapat terlalu cepat mengharapkan hasil, dan tidak boleh
lekas merasa kecewa. k. Supervisi hendaknya bersifat preventif, korektif, dan kooperatif.
Preventif berarti berusaha mencegah jangan sampai timbul hal-hal negatif; mengusahakan/memenuhi syarat-syarat sebelum terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan. Korektif berarti memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat. Kooperatif berarti bahwa mencari kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan dan usaha memperbaikinya dilakukan bersama-sama oleh supervisor dan orang-orang yang diawasi.13
Itulah prinsip-prinsip supervisi pendidikan Islam kalau dijalankan dengan profesional tentu akan meningkatkan mutu pendidikan Islam. Jika hal-hal tersebut diatas diperhatikan dan benar-benar dilaksanakan oleh pengawas, kepala sekolah/madrasah, kiranya dapat diharapkan setiap sekolah/madrasah akan berangsur-angsur maju dan berkembang mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan sekolah/madrasah. Namun, kesanggupan dan kemampuan kepala sekolah/madrasah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi berhasil tidaknya supervisi atau cepat lambatnya hasil supervisi itu, antara lain:
a. Lingkungan masyarakat tempat sekolah/madrasah berada. Apakah sekolah/madrasah itu di kota besar, di kota kecil, atau dipelosok. Di
13 M. Ngalim Purwanto, Administrasi, hal. 117
9
lingkungan masyarakat orang-orang kaya atau dilingkungan masyarakat kurang mampu. Di lingkungan masyarakat intelek, pedagang, petani, dan lain-lain.
b. Besar-kecilnya sekolah/madrasah yang menjadi tanggung jawab kepala sekolah/madrasah. Apakah sekolah/madrasah itu merupakan sekolah/madrasah yang besar, banyak jumlah guru/ustadz, murid/santrinya, memiliki halaman dan tanah yang luas, atau sebaliknya.
c. Tingkatan dan jenis sekolah/madrasah. Apakah sekolah/madrasah yang dipimpin itu MI/SD, MTs/SMP, MA/SMA, dan SMK, semuanya memerlukan sikap dan sifat supervisi tertentu.
d. Keadaan guru/ustadz dan pegawai yang tersedia. Apakah guru-guru/ustadz di sekolah/madrasah itu pada umumnya sudah berwewenang, bagaimana kehidupan sosial-ekonomi, hasrat kemampuannya, dsb.
e. Kecakapan dan keahlian kepala sekolah/madrasah itu sendiri Itulah diantara faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan supervisi yang dilaksanakan. Kalau supervisor dalam hal ini kepala sekolah/madrasah tanggap dan cepat mengambil tindakan akan mempengaruhi keberhasilan supervisi dalam peningkatan mutu pendidikan Islam. E. PERAN SUPERVISI DALAM MENINGKATKAN MUTU
PENDIDIKAN ISLAM Peran supervisi adalah keikutsertaan atau kiprah seseorang dalam suatu
hal (menyangkut potensi yang dimiliki), kaitannya dalam hal ini adalah peran supervisor adalah orang yang memiliki profesi atau pembinaan dalam bimbingan terhadap perbaikan mutu pendidikan. Pembinaan tersebut diberikan kepada seluruh staf sekolah/madrasah agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik.
Peran menurut Getzels (1967),”That roles are defined in terms of role expectations-the normative rights and duties that define within limits what a person should or should not do under various circumstances while he is the incumbent a particular role within an institution. Dari pendapat Getzels tersebut, maka peran yang bersifat kebenaran normatif dan menetapkan batasan-batasan kewajiban-kewajiban apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan seseorang secara khusus di dalam suatu organisasi. Oleh sebab itu, setiap kita bicara tentang peran seseorang dalam suatu organisasi termasuk juga organisasi sekolah/madrasah tentunya, selalu berupa peranan-peranan normatif atau ideal-ideal saja.
Peran adalah aspek dinamis yang melekat pada posisi atau status seseorang di dalam suatu organisasi seperti yang dinyatakan oleh Lipham & Hoeh (1974), “We indicate that a role is a dynamic aspect of position, office, or status in institution”. Karena peran bersifat dinamis, maka ia berkembang terus sesuai
10
dengan tuntutan kebutuhan organisasi (termasuk di dalamnya lembaga pendidikan Islam). Peran supervisor menurut Wiles & Bondi (2007) “ The role of the supervisor is to help teachers and other education leaders understand issues and make wise decision affecting student education. Bertitik tolak dari pendapat Wiles & Bondi tersebut, maka peran supervisor adalah membantu guru-guru dan pemimpin-pemimpin pendidikan untuk memahami isu-isu dan membuat keputusan yang bijak yang mempengaruhi pendidikan siswa. Untuk membantu guru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta meningkatkan prestasi belajar siswa.14 Adapun peran umum supervisor adalah sebagaimana berikut:
a. Observer (pemantau) b. Supervisor (penyelia) c. Evaluator (pengevaluasi) pelaporan, dan d. Successor (penindak lanjut hasil pengawasan).
Dalam praktiknya, orang sering menyamakan antara arti pengevaluasian dengan penilaian. Padahal, arti pengevaluasian berbeda dengan penilaian. Pengevaluasian pendidikan ialah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan penilaian proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa. Peran sebagai penyelia melaksanakan supervisi. Peran supervisi meliputi: (1) supervisi akademik, (2) supervisi manajerial. Kedua supervisi harus dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas sekolah/madrasah. Dalam melaksanakan supervisi akademik, supervisor hendaknya memiliki peran khusus sebagai:
a. Partner (mitra) guru dalam meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran dan bimbingan di sekolah/madrasah binaannya.
b. Innovator dan pelopor dalam mengembangkan inovasi pembelajaran dan bimbingan di sekolah/madrasah binaannya.
c. Konsultan pendidikan dan pembelajaran di sekolah/madrasah binaannya.
d. Konselor bagi guru dan seluruh tenaga kependidikan di sekolah/madrasah.
e. Motivator untuk meningkatkan kinerja guru dan semua tenaga kependidikan di sekolah/madrasah.15 Dalam melaksanakan supervisi manajerial, pengawas sekolah/madrasah
memiliki peranan khusus sebagai: a. Konseptor yaitu menguasai metode, teknik dan prinsip-prinsip supervise
dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah/madrasah.
14 Jerry H. Makawimbang, Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan, (Bandung: ALFABETA, 2011), hal. 78
15 Ibid, hal. 79
11
b. Programer yaitu menyusun program kepengawasan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan program pendidikan di sekolah/madrasah.
c. Komposer yaitu menyusun metode kerja dan instrument kepengawasan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawas di sekolah/madrasah.
d. Reporter yaitu melaporkan hasil-hasil pengawasan dan menindaklanjutinya untuk perbaikan program pengawasan berikutnya di sekolah/madrasah.
e. Builder, yaitu: 1). Membina kepala sekolah/madrasah dalam pengelolaan (manajemen)
dan administrasi sekolah/madrasah berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan sekolah/madrasah.
2). Membina guru dan kepala sekolah/madrasah dalam melaksanakan bimbingan konseling di sekolah/madrasah, yaitu: a). Supporter yaitu mendorong guru dan kepala sekolah/madrasah
dalam merefleksikan hasil-hasil yang dicapai untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pokoknya di sekolah/madrasah.
b). Observer yaitu memantau pelaksanaan standard nasional pendidikan di sekolah/madrasah.
c). User yaitu memanfaatkan hasil-hasil pemantauan untuk membantu kepala sekolah/madrasah dalam menyiapkan akreditasi sekolah/madrasah.
Uraian diatas, memaparkan tentang peran supervisi pendidikan tentu didalamnya ada supervisor (pengawas, kepala sekolah) dalam melaksanakan supervisi pendidikan di sekolah. Peran supervisi tersebut kalau dilaksanakan dengan profesional dan prosedural akan meningkatkan mutu pendidikan Islam yaitu, diantaranya menhasilkan pebelajar dengan hasil belajar yang baik. Kalau tidak dilaksanakan dengan baik, akan menghasilkan pebelajar yang biasa dan bahkan menghasilkan pebelajar yang kurang baik. Mengingat, mutu pendidikan Islam juga mengalami penurunan. Dari sinilah diperlukan peran supervisi pendidikan Islam yang profesional agar mutu pendidikan dapat diraih. Kita harus mampu menunjukan pada masyarakat bahwa lembaga pendidikan Islam merupakan lembaga pendidikan yang baik berdasarkan bukti-bukti riil, baru kita menunjukan kepada publik. Lembaga pendidikan Islam harus mampu menjadikan anak yang asalnya lambat menjadi anak yang pandai melalui berbagai terobosan strategis.
Dengan demikian, manajer (kepala sekolah/madrasah) harus mampu berkosentrasi dan mensupervisi pada upaya menjadikan input yang baik melalui proses yang sangat baik untuk menghasilkan output yang unggul/istimewa: input yang sedang melalui proses yang istimewa menghasilkan output yang baik sekali; dan input yang rendah melalui proses
12
yang sangat istimewa menghasilkan output yang baik.16 Lebih jelasnya dapat diperhatikan melalui tabel berikut ini:
Tabel I
Usaha Memproses Peserta Didik Menjadi Lebih Baik
No Keadaan Input Keadaan Proses Keadaan Output
1 Baik Sangat Baik Unggul/Istimewa
2 Sedang Istimewa Baik Sekali
3 Rendah Sangat Istimewa Baik
Bila kepala sekolah/madrasah, pimpinan perguruan tinggi Islam,
maupun kyai pesantren mampu mewujudkan perubahan pada pebelajar yaitu peserta didik/santri/mahasiswa dari baik menjadi istimewa, dari sedang menjadi baik sekali, dan dari rendah menjadi baik, maka mereka telah mampu menghadirkan pendidikan yang sejati. Mereka merupakan para “pahlawan” pendidikan. Sebab, jati diri pendidikan sesungguhnya terletak pada kemampuan mengubah kondisi peserta didik/santri/mahasiswa menjadi lebih baik lagi. Berdasar uraian tersebut peranan supervisi pendidikan sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam, yaitu kepala sekolah/madrasah mampu memperankan supervisi pendidikan secara profesional. F. TIPS DAN TRIK SUPERVISI DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN
ISLAM Terdapat beberapa tips dan trik yang harus dilakukan oleh supervisor
atau kepala sekolah/madrasah dalam melaksanakan supervisi di sekolah/madrasah, yaitu:
a. Membangun Kesadaran Setiap ustadz/guru dan staf sekolah/madrasah lainnya harus menyadari tugas dan fungsinya masing-masing; bahwa mereka memiliki peran penting dalam mengembangkan pribadi-pribadi peserta didik/santri. Harus disadari bahwa pengembangan pribadi peserta didik/santri ini merupakan suatu proses penyiapan generasi bangsa, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat, yang bisa bersaing, bersanding, bahkan bertanding dengan negara-negara lain.
b. Meningkatkan Pemahaman Setelah setiap ustadz/guru memiliki kesadaran yang tinggi terhadap tugas
dan fungsinya masing-masing, langkah berikutnya adalah meningkatkan pemahaman mereka agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya
16 Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam, (T.t : Erlangga, 2007), hal. 208
13
tersebut dengan baik dan efektif. Melalui pemahaman yang baik akan sangat membantu ustadz/guru dalam mengembangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar sesuai dengan bidangnya masing-masing.
c. Kepedulian Tips dan trik berikutnya dalam menghadapi supervisi pendidikan adalah menumbuhkan kepedulian dikalangan ustadz/guru dan staf lainnya, sehingga mereka peduli terhadap peserta didik/santri dan lingkungannya. Kepedulian diharapkan akan menumbuhkan sikap positif di kalangan ustadz/guru dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
d. Komitmen Tips keempat yang harus dilakukan ustadz/guru dan staf lainnya dalam menghadapi supervisi pendidikan adalah menumbuhkan komitmen yang tinggi dalam diri kita sebagai ustadz/guru, sehingga memiliki rasa aman, nyaman, dan menyenangkan dalam mengemban tugas dan fungsinya. Komitmen ini merupakan janji yang tinggi bahwa seseorang akan mengabdi diri dalam dunia pendidikan dengan sungguh-sungguh dalam keadaan (situasi dan kondisi) apapun.
Uraian diatas adalah tips dan trik dalam melaksanakan supervisi pendidikan, supervisor (pengawas, kepala sekolah/madrasah) harus mempunyai tips dan trik yang tepat agar pelaksanaan supervisi pendidikan dapat berjalan optimal sehingga peningkatan mutu pendidikan Islam dapat terwujud. G. KESIMPULAN
Permasalahan mutu di lembaga pendidikan Islam merupakan permasalahan yang paling serius dan paling kompleks. Rata-rata, lembaga pendidikan Islam belum ada yang berhasil merealisasikan mutu pendidikannya. Padahal mutu pendidikan itu menjadi cita-cita bersama seluruh pemikir dan praktisi pendidikan Islam, bahkan telah diupayakan melalui berbagai cara, supervisi, metode, pendekatan, strategi, dan kebijakan.
Dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam masalah mutu harus menjadi perhatian utama semua pihak, agar lembaga pendidikan Islam dapat eksis dan solid serta hidup berkelanjutan dalam era global. Tuntutan terhadap mutu oleh para pengelola lembaga pendidikan Islam(kyai, kepala sekolah/madrasah, ustadz, guru, karyawan) dan pengguna (orang tua, masyarakat) merupakan suatu semangat yang besar dan kebanggaan. Masalah mutu dalam lembaga pendidikan Islam merupakan kebutuhan yang harus disampaikan dan dirasakan oleh para santri, siswa, guru, ustadz, orang tua, masyarakat, dan para stakeholders.
Untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam peran supervisi pendidikan tidak boleh diabaikan. Sebab supervisi merupakan hal yang signifikan dalam mewujudkan mutu tersebut. Supervisor (pengawas, kepala
14
sekolah/madrasah) harus mempunyai kepiawaian dan keseriusan dalam mensupervisi lembaga pendidikan Islam dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Islam. Diantaranya supervisor menerapkan prinsip-prinsip supervisi, memperankan supervisi, dan menggunakan trik dan tips supervisi pendidikan secara profesional. Disamping itu, kyai, kepala sekolah/madrasah, ustadz/guru, karyawan sekolah/madrasah berusaha keras mewujudkan perubahan pada pebelajar yaitu peserta didik/santri/mahasiswa dari baik menjadi istimewa, dari sedang menjadi baik sekali, dan dari rendah menjadi baik. Wallahu’alamu bissawab.
BIBLIOGRAFI Arikunto, Suharsimi., Dasar-Dasar Supervisi, Cet. I, Jakarta: Rineka Cipta, 2004 Asiaweek, Political and Ekonomic Risk Consultancy (Online). Tersedia: www.
Cnn./AsiaNow/Asiaweek, 2000 Asiaweek, Quality in Higher Education of Indonesia (Online), Tersedia: www.
Cnn./Asiaweek, 2000 Baharuddin, Moh. Makin, Manajemen Pendidikan Islam Transformasi Menuju
Sekolah/Madrasah Unggul, Malang: UIN-Maliki Press, 2010 Crosby, P.B, Quality in Free, New York: McGraw Hill Book Inc, 1979 Depdiknas, Petunjuk Pengelolaan Adminstrasi Sekolah Dasar, Jakarta: Depdiknas,
1997 Depdiknas, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, (Buku 1). Jakarta:
Depdiknas, 2001 Deming, W.E, Out of Crisis, Cambridge: Massachussets Institute of
Technology, 1982 Fullan & Stiegerbauer, The New Meaning of Educational Change, Boston:
Houghton Mifflin Company, 1991 Feigenbaum, Total Quality Control, New York: McGraw Hill Book Inc, 1986 Garvin dan Davis, A, Management Quality, New York: The Free Press, 1994 Gunawan, Ary H., Administrasi Sekolah Administrasi Pendidikan Mikro, Cet. I,
Jakarta: Rineka Cipta, 2002 Hadis, Abdul, Nurhayati, Manajemen Mutu Pendidikan, Bandung: ALFABETA,
2010 Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers,
2005 Juran, J.M, Quality Planning and Analysis, New York: McGrraw Hill Book Inc,
1993 Makawimbang, Jerry H, Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan, Bandung:
ALFABETA, 2011 Mulyasa, E, Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah, Jakarta: Bumi Aksara,
2011
15
Nasution, S, Sosiologi Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, 1994 Purwanto, M. Ngalim, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, Cet. Xix, Bandung:
Rosdakarya, 2009 Qomar, Mujamil, Manajemen Pendidikan Islam Strategi Baru Pengelolaan Lembaga
Pendidikan Islam, Erlangga, 2007 Sahertian, Piet A, Konsep-Konsep dan Teknik Supervisi Pendidikan Dalam Rangka
Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta: Rineka Cipta, 2000 Sallis, Edward, Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan, Yogyakarta: IRCiSod, 2010 Supandi, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, Jakarta: Departemen Agama
Universitas Terbuka, 1996 Supriadi, Dedi, Mengangkat Citra dan Martabat Guru, Yogyakarta: Adicita Karya
Nusa, 1999 Suprihatin, MD, Administrasi Pendidikan Fungsi dan Tanggung Jawab Kepala
Sekolah sebagai Administrator dan Supervisor Sekolah, Semarang: IKIP Semarang Press, 1989
Surya, Mohamad, Peran Organisasi Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, Seminar Lokakarya Internasional, Semarang : IKIP PGRI, 2002
Suryasubrata, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, Jakarta: Rineka Cipta, 1997 Sulistyorini, Manajemen Pendidikan Islam Konsep Strategi dan Aplikasi,
Yogyakarta: TERAS, 2009
1
NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM KISAH YUSUF (PENAFSIRAN H.M. QURAISH SHIHAB ATAS SURAH YUSUF)
A.M. Ismatullah
Abstract ;
This paper aims to explore the educational values embodied in the story of Yusuf and its relevance in the present life by virtue of the interpretation of the story of yusuf Quraish Shihab al-Misbah in interpretation. From the research results can be concluded that the educational values embodied in the story of Yusuf and its relevance in the present life of them: first, an attitude of openness and communication is established between the child and the father is between Yusuf and Ya'qub, secondly, the wisdom of the head of the family; the third, King fair / Upholding justice, this can be seen in paragraph 43 letter to Joseph, who hinted that the head of state or the king of Egypt at that time to be fair and not arbitrary; Fourth, demand for office / professional. This can be reflected in the letter of Yusuf verse 55 "Yusuf says : Let me state treasurer (Egypt) because actually I was the smart guard, more knowledgeable. And fifth, yusuf patience in the face and pass the trials that befall him. Key Words : Nilai Pendidikan, Kisah Yusuf A. PENDAHULUAN
Bagi umat Islam, Al-Qur'an diyakini merupakan kitab suci yang menjadi pegangan hidup yang diwahyukan Allah kepada umat manusia melalui perantara Nabi Muhammad s.a.w. sebagai penutup para Nabi dan Rasul.1 Sebagai kitab Allah terakhir yang diturunkan, Al-Qur'an memuat ajaran-ajaran yang begitu lengkap, universal dan integral. Ia telah mencakup dan menyempurnakan pesan-pesan Allah pada umat sebelumnya. Ada mata rantai pesan-pesan Ilahi dalam wahyu Allah yang disampaikan kepada umat manusia melalui para Nabi. Di dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa Al-Qur'an sesungguhnya merupakan bagian integral dari induk al-Kitāb (ummul kitāb) yang ada di sisi Allah, transendental dan penuh hikmah.2
Di sisi lain Al-Qur'an juga merupakan aż-Żikr3 yaitu sebagai peringatan dari Allah bagi semua umat manusia yang berkaitan dengan permasalahan
Penulis adalah dosen tetap jurusan Tarbiyah STAIN Samarinda, lulusan
pascasarjana UIN Sunan Kalijaga tahun 2006 1 Nurcholis Madjid, Islam Agama Peradaban "Membangun Makna dan Relevansi Doktrin
Islam dalam Sejarah" (Jakarta: PARAMADINA, 2000),.hal. 3. 2 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: tpn, 1971), hal.794.
QS. az-Zuhruf: 4, yang artinya: Dan sesungguhnya Qur'an itu dalam induk al-Kitab (ummul Kitāb) di sisi Kami adalah benar-benar tinggi (nilainya) dan amat banyak mengandung hikmah.
3 Q.S. al-Hijr/15:9 yang artinya: Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan al-Qur'an (az-Żikr) dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.
2
hukum, peristiwa-peristiwa masa lampau yang dapat dijadikan pelajaran dalam menjalani kehidupan. Berkaitan dengan hal ini Arkoun menulis:
“Pengertian ummu al-kitāb yang transenden, penuh dengan hikmah dan dipelihara di sisi Tuhan sangat penting untuk menentukan secara akurat status al-Qur'ān yang dipahami sebagai bacaan-bacaan yang diartikulasikan dalam bahasa Arab untuk menjelaskan secara gamblang kepada umat manusia kebenaran-kebenaran dan perintah-perintah yang dipilih oleh Tuhan untuk mengingatkan orang-orang yang berdosa sebagaimana Ia lakukan terhadap Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w.”4
Untuk menyampaikan peringatan-peringatan dan mendidik umat
manusia, Al-Qur'an menggunakan berbagai macam bentuk. Salah satu di antara bentuk yang dipilihnya adalah pemaparan kisah-kisah yang menggambarkan peristiwa kehidupan umat terdahulu.
Dari segi proporsi, kisah menempati bagian terbanyak dalam keseluruhan isi Al-Qur'an. Kisah dituturkan sebagai media penyampaian pesan kepada umat manusia tentang perlunya usaha terus menerus untuk meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai puncak ciptaan Ilahi.5
Kisah dalam Al-Qur'an mencakup pembahasan tentang akhlak yang dapat mensucikan jiwa, memperindah watak, menyebarkan hikmah dan keluhuran budi. Kisah dalam Al-Qur'an disampaikan dalam berbagai bentuk, bentuk dialog, metode hikmah dan ungkapan, atau menakut-nakuti dan peringatan, sebagaimana terkandung dalam sebagian besar sejarah rasul-rasul beserta kaumnya, bangsa-bangsa dan para penguasanya, kisah kaum yang mendapat petunjuk, dan kisah kaum yang sesat. Semua itu ditegaskan oleh AlQur'an untuk diambil maknanya, direnungi dan dipikirkan sebagai sumber pelajaran.6 Kisah-kisah al-Qur'an disebut sebagai "sebaik-baik kisah"7dan merupakan kisah-kisah kebenaran.8
Kisah dalam Al-Qur'an merupakan salah satu bentuk yang cukup strategis dalam menyampaikan peringatan Allah dan menanamkan pesan-pesan wahyu termasuk nilai-nilai pendidikan ke dalam jiwa seseorang tanpa ada unsur paksaan. Pesan-pesan itu diterima dengan perasaan senang dan kesadaran.
Tidaklah mengherankan jika Al-Qur'an menyatakan dengan bahasa yang tegas tentang perlunya manusia bercermin ke masa lampau untuk mengambil pelajaran dari kisah-kisah umat terdahulu.9
Diantara kisah-kisah pilihan yang terdapat di dalam Al-Qur'an, adalah kisah Nabi Yusuf a.s. Sebuah kisah yang sungguh unik jika dibandingkan
4 Mohammed Arkoun, Rethinking Islam, terj. Yudian W. Asmin dan Lathiful Khuluq
(Yogyakarta: LPMI dan Pustaka Pelajar, 1996),.hal. 48. 5 Nurcholis Madjid, Islam, hal, 45. 6 Ibid. Lihat QS. al-A'raf/7: 173; QS. Yūsuf/12: 111. 7 Lihat QS. Yūsuf/12: 3 8 Lihat QS. Ali Imrān/3: 62. 9 Bey Arifin, Rangkaian Cerita dalam al-Qur'an (Bandung: al-Ma'arif, 1995), hal. 5.
3
dengan kisah-kisah Nabi lainnya.Pertama, kisah Nabi Yusuf a.s ini khusus diceritakan dalam satu surat, dan satu surat ini hanya berisi rangkaian cerita kisah Yusuf tidak ada bagian lain seperti permasalahan tasyri', sedang kisah Nabi-nabi yang lain disebutkan dalam beberapa surat. Kedua, isi dari kisah Nabi Yusuf a.s. ini berlainan pula dengan kisah Nabi-nabi yang lain. Dalam kisah Nabi-nabi yang lain, Allah menitik beratkan kepada tantangan yang bermacam-macam dari kaum mereka, kemudian mengakhiri kisah itu dengan kemusnahan para penentang para Nabi itu. Sedangkan dalam kisah Nabi Yusuf a.s. Allah swt menonjolkan akibat yang baik dari pada kesabaran, dan bahwa kesenangan itu datangnya sesudah penderitaan10.
Untuk mengetahui rentetan kisah yusuf penulis menggunakan kitab
tafsir al-Mis bāh karya Quraish Shihab. Hasil penelaahan penulis terhadap tafsir
al-Mis bāh ternyata Quraish Shihab dalam menafsirkan rentetan kisah Yusuf tidak menafsirkan secara keseluruhan dalam satu bagian, tetapi ia membaginya dalam beberapa bagian yang disebutnya dengan "episode". Quraish Shihab membagi rentetan kisah Yusuf ke dalam sepuluh episode, yang dimulai dengan episode "mimpi seorang anak" sampai episode terakhir yaitu "i'tibar dari kisah Nabi Yusuf as".11
Quraish Shihab menyatakan dalam tafsirnya bahwa surah Yusuf merupakan surah yang unik, dimana surah ini menguraikan suatu kisah secara sempurna yang menyangkut satu pribadi dalam banyak episode. Bahkan Quraish Shihab menyatakan, jika kita ingin mengetahui bagaimana memaparkan kisah yang Islami dan bermutu, maka perhatikanlah surah ini.12
Tulisan ini akan mencoba menggali nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam kisah Yusuf dan relevansinya dalam kehidupan sekarang yang dipaparkan Quraish Shihab dalam tafsirnya.
B. PENGERTIAN DAN MACAM-MACAM KISAH AL-QUR'AN
Secara etimologi, kata kisah berasal dari bahasa Arab al-Qissah bentuk jamaknya adalah al-Qasas13 yang berarti kejadian masa lampau,14 periwayatan khabar, khabar yang dikisahkan, jejak, sesuatu yang tertulis, kejadian, masalah dan keadaan.15
10 Departemen Agama RI, Al-Qur'an, hal. 366. 11 Quraish Shihab, Tafsir al-Mis bāh "Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an" Vol. 6
(Jakarta: Lentera Hati, 2004), hal. 375-515. 12 Quraish Shihab, Tafsir al-Mis bāh "Pesan, hal. 377. 13 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progressif,
1997), hal. 1126. 14 Louis Ma'luf, Al-Munjid, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1975), hal. 631. 15 `Ibrahim Anis, dkk, Al-Mu'jām al-Wasit, Jilid II, ( Beirut: Dār al-Fikr, tt.), hal. 739-
740.
4
Menurut Manna Khalil al-Qattan kisah berarti tattabi' al-Aśar (penyelidikan jejak)16. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Kahfi ayat 64.
فارتدا على اثارمها قصصاArtinya: Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula.17
Ayat ini menjelaskan bahwa nabi Musa dan pengikutnya menyelidiki jejak yang telah mereka lalui. Dalam ayat lain surah al-Qasas ayat 11 ;
وقالت الخته قصيهArtinya: “Dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan "ikutilah
dia".18 Ayat ini menjelaskan bahwa ibu nabi Musa mengatakan kepada saudara
perempuan Musa "ikutilah jejaknya (bayi Musa)" sehingga kamu melihat orang yang mengambilnya.
Secara terminologi kisah adalah upaya mengikuti jejak peristiwa yang benar-benar terjadi atau imajinatif, sesuai dengan urutan kejadiannya dan dengan jalan menceritakannya satu episode, atau episode demi episode.19
Menurut Muhammad Kamil Hasan kisah adalah:
وسيلة لتعبري عن احلياة قطاع معني منن احليناة نتوناوا ثا ثنة واثنداة او عند منن احلن ا ث بيوها ترابط سر ي وجيب ان تك ن هلا بدانة وهنا نة
Artinya: Suatu media untuk mengungkapkan suatu kehidupan atau kejadian tertentu dari kehidupan yang mencakup satu peristiwa atau beberapa peristiwa yang mana peristiwa tersebut disusun secara runut, serta harus ada permulaan dan penutupnya.20 Menurut Ahmad Khalafullah, kisah adalah:
“ Suatu karya sastra yang merupakan hasil khayal pembuat kisah terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi atau pelaku yang sebenarnya tidak ada atau dari pelaku yang benar-benar ada, akan tetapi peristiwa yang berkisar pada dirinya dalam kisah itu tidak benar-benar terjadi atau peristiwa-peristiwa itu memang terjadi pada diri pelaku akan tetapi kisah tersebut disusun atas dasar seni yang indah, dimana sebagian didahulukan dan sebagian lain dikemudiankan, yang sebagian disebutkan dan sebagian
16 Mannā' Khalil al-Qattan, Mabāhiś, hal. 350. 17Departemen Agama RI, al-Qur'an ,hal. 454. 18 Ibid, hal. 610. 19 Quraish Shihab, Tafsir al-Misbāh, hal. 394. 20 Muhammad Kamil Hasan al-Mahami, Al-Qur'ān wa al-Qissah al-Hadisah, (Beirut:
Dār al-Buhūs, 1970), hal. 9
5
yang lain dibuang. Atau terhadap peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi itu ditambahkan peristiwa baru yang tidak terjadi atau dilebih-lebihkan penggambarannya, sehingga pelaku-pelaku sejarah keluar dari kebenaran yang biasa dan sudah menjadi para pelaku khayali.21
`Ibrahim Anis, dkk mendefinisikan kisah sebagai berikut:
ثكانة نثرنة ط نلة تستمد من ا خلياا اوال اقع اوموهما معا وتبين علي ق اعند معيونة منن الفن الكتايب
Artinya :“Hikayat dalam bentuk prosa yang didasarkan kepada khayalan atau fakta atau keduanya secara bersamaan, dan dibangun berdasarkan kaidah-kaidah seni penulisan tertentu.”22
Dari definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan secara umum kisah
mempunyai karakteristik sebagai berikut: cerita yang berbentuk prosa, ada yang bersifat khayalan dan ada yang bersifat nyata, di dalam cerita ada permulaan dan ada penutupnya.
Dalam hal ini, definisi-definisi di atas tidak sepenuhnya dapat diterapkan pada kisah-kisah dalam al-Qur'an sebab kisah dalam al-Qur'an merupakan kisah nyata bukan hasil khayalan belaka sang pembuat kisah, kemudian kisah dalam al-Qur'an tidak harus ada permulaan dan penutupnya, selain itu penyebutan kisah dalam al-Qur'an bukan semata-mata tunduk pada gaya kesusasteraan atau gaya para pembuat kisah atau metode sejarah yang ingin mensejarahkan para aktornya dari awal sampai akhir. Jika dalam al-Qur'an ada suatu kisah yang disebutkan dari awal sampai akhir itupun tidak dikisahkan secara urut dari awal sampai akhir, namun secara terpisah-pisah dalam berbagai ayat dan surat bahkan kadang kala mengalami pengulangan.
Metode yang digunakan al-Qur'an dalam penyebutan kisah tidak seperti metode penyebutan kisah pada umumnya. Sebagai mana dikemukakan oleh Rasyid Ridha dalam tafsir al-Manār, bahwa al-Qur'an tidak terikat oleh susunan yang dipakai oleh ahli sejarah dan cara-cara penulis dalam menyusun pembicaraan dan mengaitkan sesuai cara terjadinya peristiwa sehingga menjadi peristiwa yang menyatu.23
Metode kisah dalam al-Qur'an tunduk pada tujuan agama, yang dalam menyebutkan kisah-kisahnya sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu kadang kala kisah itu hanya disebutkan terpisah-pisah atau sebagian saja dan kadang pula di ulang-ulang. Dengan demikian tidak hanya ada permulaan dan penutupnya sebagaimana penyebutan kisah pada umumnya. Demikianlah
21 Muhammad A Khalafullah, Al-Fann al-Qasas Fi al-Qur'ān (Mesir: Maktabah al-
Masriyah, 1972), hal. 119. 22 `Ibrahim Anis, dkk, al-Mu'jām, hal. 740. 23 Rasyid Ridha, Tafsir al-Manār, Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), hal. 346.
6
antara lain sebab al-Qur'an tidak dapat disebut sebagai kitab kisah, meskipun di dalamnya banyak terdapat kisah.
Penggunaan kata kisah dalam al-Qur'an dengan bentuk jama' qisas sebanyak lima kali, yaitu terdapat dalam Surah Ali Imrān /3:62; al-A'rāf /7: 176; Yūsuf /12: 3; al-Kahfi /18: 64 dan al-Qasas /28/25.24 Dalam al-Qur'an Allah dan para Rasul disebut sebagai sumber atau penutur kisah. Allah sebagai penutur kisah menggunakan kata ganti nahnu (Kami), di tiga belas ayat, delapan kali menggunakan fi'il mādi dan empat kali dalam bentuk fi'il mudāri'. Juga digunakan kata huwa (dia), dalam dua ayat, sekali menunjukkan al-Qur'an (QS. An-Naml/27:76). Rasul-rasul sebagai penutur kisah, adalah dalam rangka menyampaikan ayat-ayat Allah swt. Dua kali dalam bentuk fi'il mādi dan sekali dalam bentuk fi'il amr. (QS. Al-An'ām/6:130; Al-A'rāf/7:35 dan 176).25
Selain kata qisah al-Qur'an juga menggunakan kata naba', baik dalam bentuk mufrad maupun dalam bentuk jama'. Kata naba' diulang sebanyak 17 kali, di 15 surat al-Qur'an (al-Māidah/5:27; al-A'nām/6:4, 67; al-A'rāf/7:175; at-Taubah/9:70; Yūnus/10:71; `Ibrāhim/14:9; al-Kahfi/18:13; asy-Syu'arā'/26:69; an-Naml/27:22; al-Qasas/28:3; Sād/38:21,67,88; al-Hujurāt/49:6; at-Tagābun/64:5; an-Nabā/78:2. Dan dalam bentuk jama' (anba), sebanyak 12 kali, di 11 surat al-Qur'an.26 Dari ayat-ayat yang menggunakan lafaz naba, 12 kali terkait langsung dengan ayat yang mengandung kisah, dan lima kali tidak terkait dengan kisah, sedangkan ayat-ayat yang menggunakan lafaz anba, semuanya terkait langsung dengan kisah.
Allah swt. juga dapat disebut sebagai sumber dan penutur berita, dengan mendasarkan pada kata yunabbiukum dan yunabbbiuhum. Kata yunabbiukum berulang sembilan kali yang ada di enam surat (QS. Al-Māidah/5:48 dan 105; al-An'ām/6:60 dan 164; at-Taubah/9:94 dan 105; Sabā'/34:7; az-Zumār/39:7; al-Jumu'ah/62:8) dan kata yunabbiuhum berulang enam kali yang ada di empat surat (QS. Al-Māidah/5:14; al-An'ām/6:108 dan 159; an-Nūr/24:64; al-Mujadalah/58:6-7).27Ayat-ayat tersebut terkait langsung dengan Allah sebagai penutur berita, kecuali satu ayat QS. Sabā'/34:7 yang menunjuk pada Nabi Muhammad saw, ketika menyampaikan berita hari kebangkitan kepada orang-orang kafir.
Dari segi terminologi, qisah dimaksudkan sebagai "suatu fragmen atau potongan-potongan dari berita-berita tokoh atau ummat terdahulu".28
24 Muhammad Fuad Abd al-Bāqi, Al-Mu'jām al-Mufahras al-Alfāż al-Qur'ān al-Karim
(Tk: Dār al-Fikr, 1981), hal. 542. 25 Radhi al-Hafiz, Nilai Educatif Kisah al-Qur'an, Disertasi Program Pasca Sarjana
IAIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1995), hal. 10. 26 Muhammad Fuad Abd al-Bāqi, Al-Mu'jam, hal.. 686. 27 Ibid., hal. 685. Dikutip dari Siti 'Aisyah, Ayat-ayat al-Qur'an tentang Kisah Perempuan,
(Studi tentang Makna Pendidikan dan Pelaksanaannya pada Masa Rasulullah Muhammad saw), Tesis Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta: UIN Suka, 2004),hal. 29.
28 Syihabuddin Qalyubi, Stilistika Al-Qur'an; Pengantar Orientasi Studi Al-Qur'an (Yogyakarta:Titian Ilahi Press, 1997), hal. 66.
7
Menurut Manna Khālil al-Qattān kisah al-Qur'an adalah: “Kisah al-Qur'an adalah berita yang dibawa al-Qur'an tentang keadaan ummat-ummat dan Nabi-Nabi terdahulu, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi secara empiris. Sesungguhnya al-Qur'an banyak memuat peristiwa-peristiwa masa lalu, sejarah ummat-ummat terdahulu, negara, perkampungan dan mengisahkan setiap kaum dengan bentuk yaitu seolah-olah pembaca menjadi pelaku yang menyaksikan peristiwa itu.”29
Manna Khālil al-Qattān di sini secara tegas menyatakan bahwa kisah yang terdapat di dalam al-Qur'an itu benar-benar terjadi dalam dunia nyata, bukan hanya fiktif belaka. Menurutnya, jika kisah yang terdapat di dalam al-Qur'an bersifat fiktif belaka, hal ini tentunya akan menimbulkan kesan bahwa dalam al-Qur'an itu ada kebohongan. Padahal mustahil al-Qur'an bohong terhadap apa yang diceritakannya. Kisah al-Qur'an adalah haqiqi bukan hayāli.30
Kisah-kisah yang tertulis dalam al-Qur'an berbeda dengan cerita-cerita lesan yang tersiar di masyarakat yang tertulis dalam buku-buku cerita, juga cerita pendek, cerita bersambung yang dimuat dalam majalah maupun surat kabar. Kisah dalam al-Qur'an memiliki kualifikasi kebenaran yang mutlak.
Kisah-kisah al-Qur'an memuat berita-berita ummat maupun misi kenabian yang terjadi pada masa lalu, maupun berita gaib yang terjadi pada masa pra sejarah seperti kisah Adam dan istrinya di surga, serta berita gaib tentang malaikat, iblis, surga dan neraka. Semua itu menunjukkan salah satu I'jāz atau keistimewaan al-Qur'an sebagai kodifikasi wahyu Allah. 31 Ada beberapa pendapat tentang macam-macam kisah dalam al-Qur'an, diantaranya pendapat Mannā' Khālil al-Qattan yang membagi kisah dari segi isi atau tema yang dikisahkan menjadi tiga yaitu: 1. Kisah para Nabi
Kisah ini mengetengahkan dakwah para Nabi terhadap kaumnya, mu'jizat-mu'jizatnya yang merupakan bentuk dukungan Allah atas sikap penentangnya, perjalanan dan perkembangan dakwah dan ending bagi mu'minin dan mukażżibin, seperti kisah Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Harun, ‘Isa, Muh{ammad dan lain sebagainya.
2. Kisah-kisah yang berhubungan dengan kejadian masa lalu dan tentang orang-orang yang tidak dipastikan kenabiannya. Misalnya, kisah Talut, Jalut, Ashabul Kahfi dan lain-lain.
3. Kisah-kisah yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah, seperti perang badar, uhud, tabuk, hunain, hijrah Nabi, isra' mi'raj dan lain sebagainya.32
29 Mannā' Khālil al-Qattān, Mabāhiś, hal. 306. 30 Ibid., hal 308. 31 Ibid., hal. 30-31. 32 Mannā' Khalil al-Qattān, Mabāhiś hal. 306.
8
Ditinjau dari segi panjang atau pendeknya rentetan kisah serta kelengkapan pengungkapan tokohnya, maka kisah al-Qur'an di bagai menjadi tiga: 1. Qissah Ta'wilah atau Riwāyah (Kisah panjang atau novel)
Kisah ini lebih detail dari pada kisah al-Qur'an lainnya. Dalam kisah ini disebutkan mulai dari lahirnya tokoh, perkembangannya, kehidupannya sebelum diutus menjadi Rasul, kemudian kehidupannya sebagai Nabi dan Rasul dan hubungannya dengan kaumnya serta hasil dari perjuangannya. Disela-sela kisah ini ada beberapa nasihat yang menyentuh perasaan melalui sikap-sikap tokoh kisah seperti marah, senang, ridha, cinta, benci dan lain-lainnya. Kisah semacam ini seperti kisahnya Nabi Musa, Yusuf, Sulaiman.
2. Qissah Mutawassitah (Kisah sedang) Kisah ini menyebutkan sebagian riwayat hidup tokoh atau Nabi. Ada beberapa pragmen dalam kisah ini, akan tetapi pragmen-pragmen ini tidak sedetail kisah ta'wilah. Cuplikan kehidupan tokohnya terkadang disebutkan pada awal kehidupannya, terkadang pada akhirnya. Juga disebutkan dakwahnya kepada kaumnya, sikapnya dan sikap kaumnya serta kesimpulan atau hasil dari dakwah. Kisah semacam ini seperti kisahnya Nabi Nuh, Daud dan Adam.
3. Qissah Qasirah (Kisah pendek) Kisah semacam ini pragmenya lebih sedikit dari kisah mutawassitah. Terkadang tidak lebih dua pragmen. Dalam kisah ini disebutkan dakwah rasul, sikap kaumnya akhir dakwah itu, setelah mereka mendustakan dakwahnya. Kisah semacam ini seperti kisahnya Nabi Idris, Yasa dan Zulkifli.33
Secara garis besar kisah al-Qur'an dibagi menjadi tiga yaitu: 1. Al- Qissah at-Tārikhi
Yaitu kisah yang mencerminkan kebenaran fakta.34 Peristiwa historis dalam al-Qur'an tidak disusun secara kronologis, karena tujuannya bukan semata-mata sejarahnya, akan tetapi tujuannya adalah menarik pelajaran dan memikirkan hubungan kausalitas antara peran sunnatullāh pada manusia, baik kecenderungan kepada kebaikan atau kejahatan.35 Ada beberapa hal yang membuktikan bahwa deskripsi al-Qur'an terhadap kisah-kisah sejarah adalah deskripsi sastra, yaitu: a. Dipertemukannya unsur-unsur sejarah tertentu dalam satu kisah,
dimana satu unsur dengan unsur yang lainnya terpaut oleh rentang waktu yang cukup lama.
b. Al-Qur'an sering menyematkan satu perkataan atau ungkapan kepada seorang tokoh kisah yang belum pernah diucapkan oleh tokoh tersebut.
33 Sayyid Qutb, At-Taswir al-Fanni fi al-Qur'ān (Mesir: Dār al-Ma'ārif, t.t), hal. 136-138. 34 At-Tihami Naqrah, Sikūlūjiyah al-Qur'āniyah (Al-Jazair: Asy-Syirkah at-Tunisiyah,
1971), hal. 156. 35 Ibid., hal. 176.
9
Tujuannya adalah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pendeskripsian agar lebih hidup.36
c. Al-Qur'an sering menyebutkan kejadian-kejadian khusus yang dialami oleh tokoh-tokoh tertentu dalam satu kisah, kemudian dalam kisah lain kejadian-kejadian tersebut dilukiskan kembali akan tetapi dengan tokoh yang berbeda.
Dengan kata lain, logika sastralah yang harus digunakan dalam menelaah kisah-kisah al-Qur'an, bukan logika rasional (kesejarahan) yang berorientasi pada kronologis kejadian dari kisah-kisah tersebut.37 Kisah-kisah al-Qur'an umumnya adalah kisah sejarah dengan pendekatan sastra, artinya materi kisahnya secara umum bersumber dari realitas sejarah, namun realitas tersebut direkonstruksi dengan gaya al-Qur'an yang khas dan disesuaikan dengan kultur masyarakat Arab ketika itu sehingga menimbulkan kesan dan pemaknaan baru. Sebagai contoh kisah sejarah dengan pendekatan sastra adalah kisah-kisah al-Qur'an umumnya, seperti: kisah Musa, `ibrahim, Yusuf dan sebagainya.
2. Al-Qisah al-Tamsili Yaitu kisah yang mencerminkan kebenaran tematik.38 Kebenaran yang diceritakan al-Qur'an adalah kebenaran yang tidak dapat diragukan baik yang bersumber dari peristiwa-peristiwa historis atau kenyataan hidup, dalam arti bahwa kisah itu merupakan contoh atau bentuk dasar kehidupan. Manusia tidak lepas dari kesamaan-kesamaan yang diilustrasikan dalam kisah tersebut walaupun dalam bentuk yang berbeda.
3. Al-Qissah al-Usturi Pembagian ketiga ini banyak ditentang oleh ulama, termasuk Tiham
Naqrah. Bahkan kata ini dipakai untuk menyudutkan dan menghinakan al-Qur'an oleh orang-orang musyrik Makkah. Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. an-An'am: 26.
C. NILAI-NILAI PENDIDIKAN YANG TERKANDUNG DALAM
KISAH YUSUF DAN RELEVANSINYA DALAM KEHIDUPAN SEKARANG
1. Sikap terbuka diantara Yusuf dan ayahnya Ya'qub
Sikap terbuka dan komunikasi yang baik terjalin antara anak dan ayah, terlihat ketika Yusuf mengadukan mimpinya kepada ayahnya yaitu ketika Yusuf putra Ya'qub berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku telah bermimpi melihat sebelas bintang yang sangat jelas cahayanya serta matahari dan
36 Ibid., hal. 122-129. 37 Ibid, hal. 118-124. 38 At-Tihami Naqrah, Sikūlūjiyah, hal. 156.
10
bulan, telah kulihat semuanya bersama-sama mengarah kepadaku, tidak ada selain aku dan mereka semua benda langit itu dalam keadaan sujud kepadaku seorang.39
Quraish Shihab menjelaskan bahwa apa yang disampaikan itu merupakan sesuatu yang sangat besar, apalagi bagi seorang anak kecil yang hatinya masih diliputi oleh kesucian dan kasih sayang ayahnya. Sedangkan kasih sayang ayahnya tersebut disambut pula dengan penghormatan kepada beliau. Tapi sangat disayangkan sebagai orang tua, Ya'qub kurang adil terhadap putra-putranya yang seharusnya lebih membuka diri, sehingga anak dapat mencurahkan perasaan-perasaannya dengan memperhatikan apakah ada tanda-tanda adanya perasaan yang tidak enak pada diri mereka. Di sini peran sikap adil dan bijaksana mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap mental dan kepribadian sang anak. Kalau saja Ya'qub bersikap adil dan bijaksana pada saudara-saudara Yusuf, maka mereka akan merasa diperhatikan dan merasa tidak dibeda-bedakan sekalipun dari seorang isteri yang bukan pilihannya.
Peran ayah seharusnya bisa menjaga agar perasaan (sayangnya pada Yusuf) tidak keluar sampai kelihatan atau disalahartikan oleh saudara-saudaranya. Jadi salah satu tugas orang tua yang paling kritis adalah membantu anak-anak tumbuh dengan keterampilan sosial dan kesehatan emosional. Aturan keluarga, waktu untuk diskusi dan pemecahan masalah keluarga dan niat baik serta semangat kerja sama akan menempatkan anak-anak pada jalur konstruktif positif.40Sehingga saudara-saudara Yusuf tidak akan timbul niatan jahat terhadap Yusuf.
Dalam konteks sekarang ini, sikap terbuka yang diperlihatkan oleh Yusuf sebagai seorang anak terhadap Ya'qub sebagai seorang ayah kiranya sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan berkeluarga. Dimana peran ayah sebagai orang tua sekaligus sebagai pendidik harus bisa memahami keadaan anak-anaknya, terbuka, adil dan bijaksana. Perhatian dan curahan kasih sayang seorang ayah harus bisa dirasakan oleh semua anak-anaknya. Jangan sampai ada perasaan dari sebagian anak yang merasa dibedakan.
2. Kebijaksanaan seorang kepala keluarga
Peristiwa ini bermula ketika Zulaikha seorang isteri pejabat pemerintahan di Mesir (aziz) menggoda dan mau memperkosa Yusuf, sehingga Yusuf mendapati robek bajunya ketika dia lari dari kejaran Zulaikha. Pada saat itu, suami Zulaikha memergokinya dan mendatangkan saksi terhadap kejadian tersebut. Yang mana dari hasil kesaksian tersebut Yusuf divonis tidak bersalah. Walaupun Yusuf divonis tidak bersalah, sebagai seorang kepala keluarga (aziz) mengambil suatu kebijaksanaan untuk menjaga keutuhan dan nama baik
39 Quraish Shihab, Tafsir al-Misbāh "Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an" Vol.6
(Jakarta: Lentera Hati, 2004), hal. 395. 40 Mauric J. Elias, dkk, Cara Efektif Mengasuh Anak dengan EQ (Bandung: Kaifa,
2000), hal. 54-55.
11
keluarga. Hal ini tercermin dalam perkataan Aziz (suami) tersebut ketika berkata:
"Yusuf, berpalinglah dari ini, dan engkau (hai wanita) mohonlah ampun atas dosamu..."41 Apa yang diputuskan sang suami telah menyelesaikan persoalan. Peristiwa ini, menurut Quraish Shihab, merupakan salah satu peristiwa
yang sering terjadi pada rumah-rumah keluarga "terhormat" yang kurang memperhatikan tuntunan agama. Mereka tahu dan menyadari bahwa perbuatan mereka buruk, tetapi di saat yang sama mereka ingin tampil atau paling tidak diketahui sebagai keluarga terhormat yang memelihara nilai-nilai moral. Karena itu kasus yang seperti ini harus ditutup dan dianggap seakan-akan tidak pernah ada.42.
3. Raja yang adil/Menegakkan keadilan
Menurut Quraish Shihab, penggunaan kata mālik/raja dalam ayat ke-43 surat Yusuf mengisyaratkan bahwa kepala negara atau raja di Mesir ketika itu berlaku adil dan tidak sewenang-wenang. Hal ini terbukti dengan diadakannya upaya penyelidikan terhadap kasus Nabi Yusuf, memberikan kebebasan beragama dan memberikan jabatan penting kepada orang yang berlainan keyakinan dengan sang raja untuk menjalankan tugas kepemerintahan sebagaimana yang ditugaskan kepada Yusuf
Kalau melihat konteks sekarang sifat-sifat raja tersebut kiranya sangat relevan kalau dimiliki oleh para pemimpin negara dalam rangka melaksanakan tugas kenegaraan untuk mencapai kemakmuran. Dimana masa sekarang merupakan suatu masa yang sangat kompleks sebagai sebuah sunnatullāh dengan bertambahnya usia zaman dan jumlah penduduk, maka akan bertambah pula problematika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Maka oleh karena itu seorang pemimpin haruslah mempunyai karakter-karakter sebagai berikut: 1) mempunyai sikap toleran dan menghilangkan perasaan sukuisme dengan cara menyatukan perbedaan sekaligus mengikis perasaan sektarian-isme. 2) Memiliki landasan kerjasama dan solidaritas yang diletakkan dalam kerangka yang luas. 3) mampu menghilangkan kultur organisasi baik organisasi suku, masa, sosial, politik dan lain-lain. Yang mana semua itu hanya akan menambah deretan persoalan sekaligus memperlebar jurang perbedaan. Dengan kata lain seorang pemimpin haruslah netral dalam memutuskan suatu kebijakan tanpa adanya pengaruh-pengaruh dari luar. 4) Terbuka dalam arti seorang pemimpin haruslah terbuka terhadap dinamika internal masyarakatnya. 43 5) memiliki sifat amanah.44 Pengertian amanah berarti menempatkan sesuatu
41 QS. Yūsuf (12): 29. 42 Quraish Shihab, Tafsir al-Misbāh, hal.. 439. 43 Aunur Rohim dan Iip Wijayanto, Kepemimpinan Islam (Yogyakarta: UII Press,
2001), hal. 31-32.
12
pada tempat yang wajar, seperti juga kedudukan tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang betul-betul berhak dan suatu formasi tidak diisi kecuali oleh orang-orang yang betul-betul ahli dan mampu menunaikan tugas-tugas dan kewajibannya dengan benar.
Bangsa yang tidak mengemban (mempunyai) amanat, itulah bangsa yang mempermainkan kepentingan yang telah ditetapkan, sehingga melemahkan kemampuan orang-orang yang ahli (mampu). Mereka mengabaikan tenaga-tenaga ahli untuk menetapkan orang-orang lemah yang tidak mampu (bukan tenaga ahli).45
4. Permintaan jabatan/Profesionalitas
Bermula dari mimpinya seorang raja dan meminta pertolongan kepada Yusuf untuk menafsirkan mimpinya dan apa yang ditafsirkan oleh Yusuf sang raja mempercayainya, maka Yusuf diberikan tempat oleh sang raja untuk menduduki jabatan di pemerintahannya. Maka apa yang dilakukan Yusuf kepada sang raja adalah meminta jabatan untuk ditempatkan sebagai bendaharawan. Hal ini bisa tercermin dalam surat Yusuf ayat 55 ;
" Berkata Yusuf: Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir) karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".
Apa yang dilakukan Yusuf dengan meminta jabatan kepada sang raja
dalam masa sekarang masih relevan dan sering terjadi. Permintaan jabatan yang diajukan Yusuf tidak bertentangan dengan moral agama yang meminta jabatan, permintaan ini berdasarkan pengetahuannya bahwa tidak ada yang lebih tepat dari dirinya dalam tugas tersebut dan tentunya dengan tujuan menyebarkan dakwah ilāhiah. Ayat diatas selanjutnya dapat menjadi dasar untuk membolehkan seseorang untuk mencalonkan diri atau kampanye untuk dirinya, selama motivasinya demi kepentingan masyarakat, serta merasa mampu atas jabatan tersebut. Lanjut Quraish Shihab, syarat bagi pejabat serta berlaku umum kapan dan dimana saja, yaitu memegang suatu jabatan haruslah benar-benar amat tekun memelihara amanah dan amat berpengetahuan.46.
5. Sabar
Banyak kisah-kisah di dalam al-Qur'an sering dikemukakan sebagai tamsil, itibar atau perumpamaan, agar manusia mau tafakkur, suatu refleksi religius tatkala musibah datang menimpa.47Terhadap musibah bencana yang terjadi khususnya di Indonesia, dari sekian banyak kisah Nabi, mungkin kita
44 Muhammad Abdul Aziz Al-Khuly, Akhlaq Rasulullah SAW, terj. Abdullah
Shonhadji (Semarang:Wicaksana, 1989), hal. 485. 45 Ibid., hal. 487. 46Quraish Shihab, Tafsir al-Misbāh, hal.. 489. 47 www. Kompas. Com. 2006, hal. 4.
13
bisa menarik hikmah dari kisah Yusuf sebagai cermin dari sikap kesabarannya dalam menghadapi dan melewati cobaan yang menimpanya. Kalau kita perhatikan perjalanan kehidupan Yusuf penuh dengan ujian dan cobaan. Dimulai dari disingkirkannya Yusuf oleh saudara-saudaranya sampai Yusuf harus masuk penjara dikarenakan tipu daya Zulaikha yang mau memperkosanya.Dilaluinya semua ujian dan cobaan dengan penuh kesabaran, keikhlasan, istiqomah dan selalu memohon bimbingan Allah swt. Sabar dan istiqomah itulah ternyata yang mendatangkan kesuksesan hidup dan kunci keberhasilan sebagaimana yang dialami Yusuf.
D. KESIMPULAN
Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam kisah yusuf dan relevansinya dalam kehidupan sekarang diantaranya: Pertama, Sikap terbuka dan komunikasi yang baik terjalin antara anak dan ayah, terlihat ketika Yusuf mengadukan mimpinya kepada ayahnya Ya’qub. Sikap terbuka seperti yang dicontohkan Yusuf ini sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan berkeluarga saat ini.
Kedua, Kebijaksanaan seorang kepala keluarga yaitu Peristiwa ini bermula ketika Zulaikha seorang isteri pejabat pemerintahan di Mesir (aziz) menggoda dan mau memperkosa Yusuf, sehingga Yusuf mendapati robek bajunya ketika dia lari dari kejaran Zulaikha. Pada saat itu, suami Zulaikha memergokinya dan mendatangkan saksi terhadap kejadian tersebut. Yang mana dari hasil kesaksian tersebut Yusuf divonis tidak bersalah. Walaupun Yusuf divonis tidak bersalah, sebagai seorang kepala keluarga (aziz) mengambil suatu kebijaksanaan untuk menjaga keutuhan dan nama baik keluarga. Hal ini tercermin dalam perkataan Aziz (suami) tersebut ketika berkata: "Yusuf, berpalinglah dari ini, dan engkau (hai wanita) mohonlah ampun atas dosamu”
Ketiga, Raja yang adil. Menurut Quraish Shihab, penggunaan kata mālik/raja dalam ayat ke-43 surat Yusuf mengisyaratkan bahwa kepala negara atau raja di Mesir ketika itu berlaku adil dan tidak sewenang-wenang. Hal ini terbukti dengan diadakannya upaya penyelidikan terhadap kasus Nabi Yusuf, memberikan kebebasan beragama dan memberikan jabatan penting kepada orang yang berlainan keyakinan dengan sang raja untuk menjalankan tugas kepemerintahan sebagaimana yang ditugaskan kepada Yusuf. Keempat, Permintaan jabatan/Profesionalitas. Hal ini bisa tercermin dalam surat Yusuf ayat 55 " Berkata Yusuf: Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir) karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".
Apa yang dilakukan Yusuf dengan meminta jabatan kepada sang raja dalam masa sekarang masih relevan dan sering terjadi. Permintaan jabatan yang diajukan Yusuf tidak bertentangan dengan moral agama yang meminta jabatan, permintaan ini berdasarkan pengetahuannya bahwa tidak ada yang lebih tepat dari dirinya dalam tugas tersebut dan tentunya dengan tujuan menyebarkan
14
dakwah ilāhiah. Kelima, Kesabaran Yusuf dalam menghadapi dan melewati cobaan yang menimpanya.
BIBLIOGRAFI
'Aisyah,Siti, Ayat-ayat al-Qur'an tentang Kisah Perempuan, (Studi tentang Makna Pendidikan dan Pelaksanaannya pada Masa Rasulullah Muhammad saw), Tesis Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: UIN Suka, 2004.
Al-Baqi, Muhammad Fuad Abd, Al-Mu'jām al-Mufahras al-Alfāż al-Qur'ān al-Karim, Tk: Dār al-Fikr, 1981.
Al-Hafiz, Radhi, Nilai Educatif Kisah al-Qur'an, Disertasi Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1995.
Al-Khuly, Muhammad Abdul Aziz, Akhlaq Rasulullah SAW, terj. Abdullah Shonhadji, Semarang:Wicaksana, 1989.
Al-Mahami, Muhammad Kamil Hasan, Al-Qur'ān wa al-Qissah al-Hadisah, Beirut: Dār al-Buhūs, 1970.
Anis, Ibrahim, dkk, Al-Mu'jām al-Wasit, Jilid II, ( Beirut: Dār al-Fikr, tt. Aunur Rohim dan Iip Wijayanto, Kepemimpinan Islam, Yogyakarta: UII Press,
2001. Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: tpn, 1971.
Arkoun,Mohammed, Rethinking Islam, terj. Yudian W. Asmin dan Lathiful Khuluq, Yogyakarta: LPMI dan Pustaka Pelajar, 1996. Arifin, Bey, Rangkaian Cerita dalam al-Qur'an, Bandung: al-Ma'arif, 1995.
Khalafullah, Muhammad A , Al-Fann al-Qasas Fi al-Qur'ān, Mesir: Maktabah al-Masriyah, 1972.
Madjid, Nurcholis, Islam Agama Peradaban "Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah" Jakarta: PARAMADINA, 2000.
Ma'luf, Louis, Al-Munjid, Beirut: Dar al-Masyriq, 1975. Munawwir, Ahmad Warson, Kamus Al-Munawwir, Surabaya: Pustaka Progressif,
1997. Naqrah, At-Tihami, Sikūlūjiyah al-Qur'āniyah, Al-Jazair: Asy-Syirkah at-
Tunisiyah, 1971. Purwanto,Yadi, Memahami Mimpi Perspektif Psikologi Islami, Yogyakarta: Menara
Kudus, 2003. Qalyubi, Syihabuddin, Stilistika Al-Qur'an; Pengantar Orientasi Studi Al-Qur'an
Yogyakarta:Titian Ilahi Press, 1997. Qutb,Sayyid, At-Taswir al-Fanni fi al-Qur'ān, Mesir: Dār al-Ma'ārif, t.t. Ridha, Rasyid, Tafsir al-Manār, Juz II Beirut: Dār al-Fikr, tt.
Shihab,Quraish, Tafsir al-Mis bāh "Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an" Jakarta: Lentera Hati, 2004.
15
WElias, Mauric J, dkk, Cara Efektif Mengasuh Anak dengan EQ, Bandung: Kaifa, 2000.
WWW. Kompas. Com. 2006.
PENILAIAN ACUAN PATOKAN (PAP) DI PERGURUAN TINGGI
(PRINSIP DAN OPERASIONALNYA)
Etty Nurbayani *
Abstract;
Criterion Referenced Grading (CRG), where grading is determined based on the absolute standard, it is very good or very compatible to be applied in formative tests where lecturers want to find out to what extend the students “have been formed/shaped”. after joining courses in the certain period. CRG is oriented based on success standard or passing grade which is certain. By applying CRG, lecturers can find out number of the students who have high, moderate, and low level of mastery. Therefore, the lecturer can do required efforts to achieve instructional objective optimally. Key Words : Penilaian Acuan Patokan (PAP), Perguruan Tinggi A. PENDAHULUAN
Seringkali pengembang intruksional termasuk pengajar menyusun tes setelah proses instruksional berakhir. Ia menyusunnya dalam waktu yang singkat berdasarkan isi pelajaran yang telah diajarkan dan masih segar dalam ingatannya. Keadaan yang seperti itu sangat memungkinkan tidak berfungsinya tujuan intruksional yang telah dirumuskannya. Tes yang disusunnya mungkin konsisten dengan isi pelajaran, tetapi tidak konsisten dengan perilaku yang seharusnya diukur.
Tes yang seharusnya disusun adalah tes yang mengatur tingkat pencapaian mahasiswa terhadap perilaku yang terdapat dalam tujuan intruksional. Tes tersebut mungkin tidak dapat mengukur penguasaan mahasiswa terhadap seluruh uraian pengajar dalam proses intruksional, sebab apa yang diberikan pengajar selama proses tersebut belum tentu seluruhnya relevan dengan tujuan intruksional. Isi pelajaran bukanlah kriteria untuk mengukur keberhasilan proses pelaksanaan intruksional.
Untuk mengetahui pencapaian hasil belajar mahasiswa dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan menggunakan tes-tes dengan standar-standar tertentu sesuai dengan perkembangannya. Maka dari itu bagi seorang pengajar harus mengetahui bagaimana cara atau teknik-teknik yang baik untuk mengevaluasi mahasiswanya, sejauhmana pencapaiannya dalam menguasai materi yang disampaikan.
Suatu tes hasil belajar dapat dipakai untuk menyatakan salah satunya adalah memberikan suatu gambaran tentang tugas-tugas yang dapat atau belum dapat dilakukan oleh mahasiswa. Hasil tes jenis ini dinyatakan dengan jenis-jenis pengetahuan dan ketrampilan yang dapat diperlihatkan oleh setiap mahasiswa. Metode penafsiran seperti ini disebut mengacu kepada sebuah patokan.
* Dosen Tetap Jurusan Tarbiyah STAIN Samarinda, lulusan Program Pascasarjana UNJ
Jakarta.
Skor yang diperoleh dari sebuah tes baru akan bermakna jika ditafsirkan berdasarkan suatu patokan atau berdasarkan suatu norma. Patokan yang dikenal dalam dunia evaluasi yaitu Penilaian Acuan Kelompok (PAK) dan Penilaian Acuan Patokan (PAP). Suatu penilaian dapat dianggap sebagai PAP apabila dilengkapi dengan (1) adanya seperangkat kemampuan yang telah didefinisikan secara rinci, (2) adanya seperangkat butir yang disusun berdasarkan kemampuan yang telah didefinisikan tersebut, dan (3) adanya rentangan skor yang penafsirannya dikaitkan dengan tingkat pencapaian kemampuan itu. Pada dasarnya PAP memiliki potensi kegunaan yang berbeda. Sekarang ini beberapa lembaga termasuk Perguruan Tinggi (PT) kecenderungan menerapkan PAP dengan maksud memaksimalkan keguaan tes sebagai alat evaluasi.
Pada beberapa PT yang berhubungan dengan evaluasi khususnya dalam pengolahan skor menjadi nilai akhir banyak digunakan dalam bentuk rentang skala (0 – 4) dan huruf (A, B, C, D dan E). Kesalahan sering terjadi pada pemberian nilai akhir, di mana hasil skoring dianggap sebuah nilai akhir. Padahal seharusnya hasil skoring tersebut harus dikonversi dulu menjadi nilai akhir dalam bentuk skala yang sudah ditetapkan sebelumnya, dalam bentuk seperti yang diurai di atas.
Dalam artikel ini, penulis sedikit sharing dengan pengevaluator (testeer) lainnya di perguruan tinggi yang menerapkan PAP dalam proses evaluasinya sekaligus memberikan wacana bagi pengajar yang belum begitu memahami bagaimana mengoperasionalkan PAP. B. PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA
Sebelum membicarakan penilain hasil belajar mahasiswa, dikenalkan dua pendekatan yang berlaku dalam penilaian pembelajaran. Kedua jenis pendekatan tersebut adalah Penilaian Acuan Patokan (PAP) dan Penilaian Acuan Kelompok (PAK).
PAK yaitu pemberian nilai sekelompok mahasiswa dalam suatu proses pembelajaran didasarkan pada tingkat penguasaan di kelompok itu. Artinya pemberian nilai mengacu pada perolehan nilai di kelompok itu. Sedangkan PAP yaitu menentukan kelulusan seseorang ditentukan sejumlah patokan. Artinya kemampuan atau hasil belajar mahasiswa ditentukan oleh tercapainya kriteria. Misalnya seseorang telah menguasai pokok bahasan bilamana telah menjawab dengan betul 80% dari total butir soal yang diujikan dan ia dinyatakan lulus1.
Apakah semua yang mendapat skor 80% ke atas akan mendapat nilai yang sama? Jawabannya tergantung pada sistem penilaian yang digunakan, karena ada penilaian yang menggunanakan katagori berhasil dan tidak berhasil atau lulus dan tidak lulus, tetapi ada pula menggunakan katagori huruf. Untuk Perguruan Tinggi (PT) ada aturan yaitu Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia no 232/U/2000 yang masih dipakai hingga saat ini tentang penilaian hasil belajar
1 Asmawi Zainul dan Noehi Nasution, Penilaian Hasil Belajar (Jakarta: PAU-PPAI, 1997), hal.
146-150 (disarikan)
mahasiswa2, dalam aturan itu disebutkan pada Bab V pasal 12 ayat 3 bahwa penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf/nilai lambang A (sangat baik), B (baik), C (cukup), D ( kurang), E (buruk), yang masing-masing bernilai 4, 3, 2, 1 dan 0 dimana penilaian ini bersumber penjumlahan dari nilai tes kuis, nilai tugas, niliai kehadiran dan nilai ujian akhir semester.
C. MENSKOR DAN MENILAI
Ada 2 kegiatan yang dilakukan dosen dalam pengolah hasil evaluasi yaitu menskor dan menilai. Anas Sudijono3 mengartikan skor adalah pekerjaan menyekor (baca: memberikan angka). Sedangkan Asmawi Zainul dan Noehi Nasution4 mengartikan menskor (pengukuran) sebagai pemberian angka kepada suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh orang, hal, atau obyek tertentu menurut aturan atau formulasi yang jelas, sedangkan menilai adalah suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar baik yang menggunakan tes maupun nontes. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Suharsimi Arikunto5 yang membedakan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Arikunto menyatakan bahwa mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan satu ukuran. Pengukuran bersifat kuantitatif. Sedangkan menilai adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk. Penilaian bersifat kualitatif. Hasil pengukuran yang bersifat kuantitatif juga dikemukakan oleh Norman E. Gronlund dalam Daryanto menyatakan “Measurement is limited to quantitative descriptions of pupil behavior”. 6
Sedangkan menilai Sudijono7 mengartikan angka (juga bias huruf) yang merupakan hasil ubahan dari skor-skor yang telah dijadikan satu, atau semua upaya membandingkan hasil pengukuran terhadap patokan atau bahan pembanding yang sudah dibakukan dan hasilnya dinyatakan dengan lambang yang menyatakan nilai tertentu. Keberhasilan studi mahasiswa dinilai berdasarkan komponen-komponen yang mempengaruhinya, yaitu ujian, kehadiran, sikap mental, tugas.
Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan nana sudjana8 bahwa menilai adalah proses menentukan nilai suatu obyek dengan menggunakan ukuran atau kriteria tertentu, seperti Baik, Sedang, Jelek. Seperti juga halnya yang dikemukakan oleh Richard H. Lindeman dalam Asmawi “The assignment of one or a set of numbers to each of a set of person or objects according to certain established rules”9
2 Keputusan Mendiknas no 232/U/2000 tentang Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 3 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996) hal.
309 4 Asmawie Zainul, Penilaian Hasil Belajar, hal. 5 5 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, Cet. Ke-10 ( Jakarta: Bumi Aksara,
1993), hal. 1 6 Daryanto, Evaluasi Pendidikan. ( Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), hal. 215 7 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, hal. 311 8 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Belajar Mengajar, Cet. Ke-3, (Bandung; PT Remaja
Rosdakarya, 1992), hal. 15 9Asmawi Zainul dan Noehi, Penilaian Hasil Belajar. hal. 5
Dari uraian di atas jelas bahwa untuk sampai kepada nilai, maka skor-skor hasil test merupakan skor mentah yang perlu diolah sehingga dapat dikonversi menjadi skor yang sifatnya baku atau standar.
Kesalahan sering terjadi pada pemberian nilai akhir, di mana hasil skoring dianggap sebuah nilai akhir. Padahal seharusnya hasil skoring tersebut harus dikonversi dulu menjadi nilai akhir dalam bentuk skala yang sudah ditetapkan sebelumnya, dalam bentuk skala 1-4, skala 1-10 dan skala 1-100. berikut akan dibahas cara mengkonversi hasil skor menjadi nilai akhir.
Dalam hal pengubahan dan pengolahan skor mentah menjadi nilai standar, Anas Sudijono10 membagi 2 yaitu ; 1. Konversi memggunakan acuan, ada 2 yaitu;
a. PAP (Penilaian Acuan Patokan) yang mengacu pada kriteria atau patokan. b. PAK (Penilaian Acuan Kelompok) yang mengacu pada norma atau kelompok.
2. Konversi menggunakan berbagai skala, antara lain skala 5 atau dikenal dengan istilah huruf A, B, C, D dan F, skala Sembilan (rentang nilai mulai 1 sampai dengan 9 tidak ada nilai 10), skala sebelas (rentang nilai 1 sampai dengan 10), z score dan T score.
D. PENGUBAHAN SKOR MENTAH MENGGUNAKAN PENILAIAN
PATOKAN ACUAN (PAP) 1. Pengertian
Penilaian Acuan Patokan (PAP) adalah pendekatan penilaian yang membandingkan hasil pengukuran terhadap mahasiswa dengan patokan "batas lulus" yang ditetapkan untuk masing-masing bidang mata kuliah11.
Penilaian acuan patokan (PAP) biasanya disebut juga criterion evaluation merupakan pengukuran yang menggunakan acuan yang berbeda. Dalam pengukuran ini mahasiswa dikomperasikan dengan kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam tujuan instruksional, bukan dengan penampilan mahasiswa yang lain. Keberhasilan dalam prosedur acuan patokan tegantung pada penguasaaan materi atas kriteria yang telah dijabarkan dalam item-item pertanyaan guna mendukung tujuan instruksional
2. Tujuan Pembelajaran yang menuntut pencapaian kompetensi tertentu sebagaimana
diharapkan dan termuat pada kurikulum saat ini, PAP merupakan cara pandang yang harus diterapkan.12
Dengan PAP setiap individu dapat diketahui apa yang telah dan belum dikuasainya. Bimbingan individual untuk meningkatkan penguasaan mahasiswa terhadap materi pelajaran dapat dirancang, demikian pula untuk memantapkan apa
10 Anas Sudijono. Pengantar, hal. 312 11 Asmawi Zainul dan Noehi Nasution, Penilaian. hal. 146 12 Ign Masidjo, Penilaian Pencapain Hasil Belajar Siswa di Sekolah (Jogjakarta: Kanisius, 1995)
hal. 151
yang telah dikuasainya dapat dikembangkan. Pengajar dan setiap peserta didik (mahasiswa) mendapat manfaat dari adanya PAP.
Melalui PAP berkembang upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan melaksanakan tes awal (pre test) dan tes akhir (post test). Perbedaan hasil tes akhir dengan test awal merupakan petunjuk tentang kualitas proses pembelajaran.
PAP juga dapat digunakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kurang terkontrolnya penguasaan materi, terdapat mahasiswa yang diuntungkan atau dirugikan, dan tidak dipenuhinya nilai-nilai kelompok berdistribusi normal. PAP ini menggunakan prinsip belajar tuntas (mastery learning)13.
3. Manfaat
Menurut Payne (1974) dalam bukunya Asmawi Zainul14, penerapan PAP dapat dimanfaatkan antara lain; 1. Penempatan seseorang dalam rentetan kegiatan belajar, 2. Untuk mendiagnosis kemampuan seseorang dalam pembelajaran. Artinya informasi
yang diperoleh melalui diagnosis ini langsung dapat digunakan oleh anak didik untuk mengatur langkah apa yang harus dilakukan, atau guru dapat langsung menentukan keperluan anak didik agar proses pembelajaran membawa manfaat yang lebih bermakna bagi anak didik tersebut.,
3. Jika dilakukan secara periodik dapat digunakan untuk memonitor kemajuan setiap anak didik dalam proses pembelajaran. Secara berkelanjutan dapat diketahui status seseorang dalam satu rentetan kegiatan belajar. Akhirnya dapat memacu atau memotivasi semangat belajar siswa.,
4. Kemampuan masing-masing anak didik untuk menyelesaikan kurikulum secara kumulatif akandapat menentukan keterlaksanaan kurikulum.
4. Karakteristik PAP
Tujuan penggunaan penilaian acuan patokan berfokus pada kelompok perilaku mahasiswa yang khusus. Joesmani menyebutnya dengan didasarkan pada kriteria atau standard khusus. Dimaksudkan untuk mendapat gambaran yang jelas tentang performan peserta tes dengan tanpa memperhatikan bagaimana performan tersebut dibandingkan dengan performan yang lain. Dengan kata lain tes acuan kriteria digunakan untuk menyeleksi (secara pasti) status individual berkenaan dengan (mengenai) domain perilaku yang ditetapkan / dirumuskan dengan baik.
Pada penilaian acuan patokan, standar performan yang digunakan adalah standar absolut. Semiawan menyebutnya sebagai standar mutu yang mutlak (Criterion-referenced interpretation is an absolut rather than relative interpetation, referenced to a defined body of learner behaviors)15. Dalam standar ini penentuan tingkatan (grade) didasarkan pada skor-skor yang telah ditetapkan sebelumnya dalam bentuk persentase. Untuk mendapatkan nilai A atau B, seorang mahasiswa harus mendapatkan skor tertentu
13 M Chabib Thoha, Teknik Evaluasi Pendidikan. (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hal. 88 14 Asmawie Zainul dan Noehi Nasution. Penilaian, hal. 149-150 15Coni Semiawan, Prinsip- Prinsip dan Teknik Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan (Jakarta:
Mutiara, 1991) hal. 43
sesuai dengan batas yang telah ditetapkan tanpa terpengaruh oleh performan (skor) yang diperoleh mahasiswa lain dalam kelasnya. Salah satu kelemahan dalam menggunakan standar absolut adalah sekor mahasiswa bergantung pada tingkat kesulitan tes yang mereka terima. Artinya apabila tes yang diterima mahasiswa mudah akan sangat mungkin para mahasiswa mendapatkan nilai A atau B, dan sebaliknya apabila tes tersebut terlalu sulit untuk diselesaikan, maka kemungkinan untuk mendapat nilai A atau B menjadi sangat kecil. Namun kelemahan ini dapat diatasi dengan memperhatikan secara ketat tujuan yang akan diukur tingkat pencapaiannya.
Beberapa yang harus dipahami ketika menerapkan PAP menurut Sudijono16 antara lain; pertama hal-hal yang dipelajari mahasiswa mempunyai struktur hierarkis artinya mahasiswa mempelajari taraf selanjutnya setelah menguasai secara baik tahap sebelumnya, kedua dosen harus mengidentifikasi masing- masing taraf kompetensi setidak-tidaknya mendekati ketuntasan pencapaian tujuan, ketiga nilai yang diberikan dengan menggunakan PAP berarti menggunakan standar mutlak.
E. KONVERSI HASIL SKOR MENJADI NILAI AKHIR
Dengan pendekatan PAP maka dosen dianjurkan untuk bijak dalam menentukan grade hasil belajar.17 Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam menentukan grade (standar lulus ideal untuk masing-masing mata kuliah) diantaranya dosen mendiskusikan bersama mahasiswa, makna grade dengan ruang lingkup materi perkuliahan, hal-hal apa saja yang perlu dimasukkan dalam grade terkait misalnya dengan penampilan, kemampuan dan sebagainya. Bahwa penilaian hasil belajar mahasiswa yang diberikan untuk merepresentasikan hasil belajar secara individual bukan secara bersama. Artinya semua mahasiswa mendapatkan keputusan tentang grade hasil belajar masing-masing.
PAP dilaksanakan dengan dasar kurva normal jenis persentil.18 Besar tuntutan nilai akhir dalam persentil sangat ditentukan oleh pendapat semua dosen dan PT. Ditinjau dari tuntutan nilai akhir dalam persentil bersifat gradatif, yang menyebabkan tuntutan dalam passing scorenya tidak sama, maka Masidjo19 membedakan PAP dalam 2 tipe, yaitu; PAP tipe I menetapkan batas penguasaan materi perkuliahan dengan kompetensi minimal yang dianggap lulus dari keseluruhan penguasaan materi yakni 65% (diberi nilai cukup (6 atau C). Sedangkan PAP tipe II penguasaan kompetensi minimal yangmerupakan passing score adalah 56% dari total skor yang seharusnya dicapai diberi nilai cukup. secara visual konversi nilai dalam skala ( 0 – 4) atau huruf (A, B, C, D atau E) kedua tipe PAP di beberapa PT dalam bentuk rentang sebagai berikut;
16 Anas Sudijono, Pengantar, hal. 313-315 17 H.M Sukardi. Evaluasi Pendidikan Prinsip dan Operasionalnya. (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)
hal. 220 18 M. Chabib Thoha, Teknik, hal. 87 19 Ign Masidjo, Penilaian, hal. 153
Persentasi Jawaban % Nilai Konversi
PAP I PAP II Nilai Huruf
Standar 4
90% - 100% 80% - 89% 65% - 79% 55% - 64% Di bawah 55%
81% - 100% 66% - 80% 56% - 65% 46% - 55% Di bawah 45%
A B C D E
4 3 2 1 0
F. LANGKAH OPERASIONAL PAP
Langkah kerja untuk mengubah skor menjadi nilai dengan menggunakan PAP
sebagai berikut; 1. Masukkan skor mentah pada tabel 2. Menghitung skor menjadi nilai menggunakan rumus PAP dgn mengalikan skor
ideal 3. Membuat pedoman konversi hasil perhitungan 4. Mengubah skor menjadi nilai.
Misalkan seorang dosen memberikan tes dalam mata kuliah Strategi Belajar Mengajar, soal yang dikeluarkan sebanyak 5 butir tes esei dengan total skor yang dituntut sebesar 85, tes diikuti 28 mahasiswa dan dalam tes tersebut berhasil diraih skor-skor sebagai berikut; 72, 72, 70, 66, 74, 68, 63, 61, 57, 70, 53, 68, 45, 63, 44, 73, 59, 61, 55, 67, 80, 82, 56, 75, 77, 67, 81, 68
Langkah pengubahan skor menjadi nilai
1. Masukkan skor pada Tabel (lihat pada langkah 4) 2. Menghitung skor dengan rumus PAP
Perhitungan PAP I Nilai Perhitungan PAP II
Huruf Angka
90% x 85 = 76,5 (77) 80% x 85 = 68 65% x 85 = 55,25 (55) 55% x 85 = 46,7 (47) <55%x 85 = dibwh 47
A B C D E
4 3 2 1 0/ggl
81% x 85 = 68,85 (69) 66% x 85 = 56 56% x 85 = 47,6 (48) 46% x 85 = 39 <46%x85= di bwah 39
3. Konversi nilai:
PAP I Nilai PAP II
Huruf Angka
77 ke atas 68 – 76 55 – 67 47 – 54 47 ke bwh
A B C D E
4 3 2 1 0/ggl
69 ke atas 56 – 68 48 – 55 39 – 47
39 ke bawah
4. Ubahan Skor menjadi Nilai
Skor
PAP I PAP II
Skor
PAP I PAP II
H A H A H A H A
72 B 3 A 4 44 E 0 E 0
45 E 0 D 1 73 B 3 A 4
70 B 3 A 4 59 C 2 B 3
66 C 2 B 3 61 C 2 B 3
74 B 3 A 4 55 C 2 C 2
68 B 3 B 3 67 C 2 B 3
63 C 2 B 3 80 A 4 A 4
61 C 2 B 3 82 A 4 A 4
57 C 2 B 3 56 C 2 B 3
70 B 3 A 4 75 B 3 A 4
53 D 1 C 2 77 B 3 A 4
81 A 4 A 4 67 B 3 B 3
G. PENUTUP
Pengolahan hasil tes merupakan kegiatan lanjutan , yaitu memeriksa hasil ujian dan mencocokkan jawaban mahasiswa dengan kunci. Terdapat 2 cara dalam mengolah hasil tes, yaitu skala dan acuan. Salah satu acuan yang dikembangkan di PT adalah Penilaian Acuan Patokan (PAP).
Penilaian Acuan Patokan (PAP) adalah suatu cara menentukan kelulusan seseorang (mahasiswa) dengan menggunakan sejumlah patokan yang telah disepakati dosen dan lembaga. Bilamana seseorang (mahasiswa) telah memenuhi patokan tersebut ia dinyatakan berhasil (lulus). Tetapi sebaliknya bila seseorang belum memenuhi patokan ia dikatakan gagal atu belum menguasai bahan tersebut.
Dengan PAP dapat dikdetahui hasil belajar yang sebenarnya oleh karena normanya adalah norma ideal, dengan PAP tidak diperlukan perhitungan statistik, sehingga memudahkan dosen yang tidak menguasai metode-metode statistic serta dengan PAP hanya ada satu makna bagi satu nilai yang sama oleh karena normanya tidak bersifat nisbi.
Demikianlah artikel ringkas tentang Penilaian Acuan Patokan (PAP) dalam pengolahan nilai hasil belajar. Apa yang sudah dipaparkan adalah menurut konsep dan teori evaluasi pembelajaran sepanjang yang penulis ketahui. Kalau ada kelemahan dan kesalahan mohon kritik dan saran yang membangun. Mudah-mudahan artikel bermanfaat bagi dosen dalam mengevaluasi pembelajaran.
BIBLIOGRAFI
Arikunto, Suharsimi., Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara, 1993 Daryanto, Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta, 1999 Masidjo, Ign., Penilaian Pencapaian Hasil Balajar Siswa di Sekolah. Yogyakarta: Kanisius,
1995 Mendiknas, Keputusan Mendiknas tentang Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, 2002 Mudjijo, Tes Hasil Belajar. Jakarta: Bumi Aksara, 1995 M. Chabib Thoha, Teknik Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Rajawali Pers,1990 Sudijono, Anas., Pengantar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: PR Raja Grafindi Persada,1996 Semiawan, Coni., Prinsip- Prinsip dan Teknik Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan.
Jakarta: Mutiara, 1991 Sukardi., Evaluasi Pendidikan Prinsip dan Operasionalnya. Jakarta: Bumi Aksara, 2009 Zainul, Asmawie., Penilaian Hasil Belajar. Jakarta: PAU-PPAI, 1977
PROBLEMA PENGEMBANGAN
MORAL REMAJA DALAM PERSPEKTIF
PENDIDIKAN ISLAM
Siti Hidajatul Hidajah
Abstract :
Islamic education is basically a process of creating human being who is continue, oriented and planned in order to have future generation who is faithful, smart, and even skillful, improving manner and attitude, strengthening personality, and promoting spirit of nation so that it can create humans who can develop their own selves, and collectively responsible of national development. Therefore, two kinds of education, central which basically focus on forming inner heart which emphasize on character, attitude, and personality that responsible of moral, social and religious life; real mature human with peripheral education, human effort to have children maturity with cultural life, to make human in social and cultural aspects need to be well synergized. It does not mean both kind of education cannot meet in one point in order to have ideal human, human who is smart, skillful, and faithful based on the underlying philosophy of our states.
Key Words : Pendidikan Islam, Prinsip Pendidikan Islam, Moral Remaja, Dinamika
Psikologi Remaja
A. PENDAHULUAN
Pembicaraan masalah pendidikan, apalagi pendidikan yang dikaitkan dengan agama Islam dalam konteks proses integrasi sistem nasional menghadapkan kita pada suatu kompleksitas permasalahan yang klasik, fundamental tetapi aktual. Klasik karena masalah pendidikan sudah timbul sejak manusia sadar untuk mencari arti akan kehadirannya dalam kehidupan di dunia ini. Fundamental karena masalah pendidikan selalu menyangkut “penempaan” manusia untuk dipersiapkan ke masa depan tertentu yang secara subyektif menuntut untuk dipilih di masa kini. Dan aktual karena masalah agama juga masalah pendidikan, dirasakan sebagai sarana utama dan potensial dalam proses integrasi sistem nasional yang tidak pernah mengenal titik henti, sejalan dengan perkembangan waktu dan kebutuhan.
Tiap bangsa dan tiap zaman mempunyai persepsi dan orientasi sendiri-sendiri dalam menentukan gagasan-gagasan vital yang berupa nilai-nilai agama ataupun nilai moral untuk dijadikan dasar dan arah dalam pengelolaan lembaga pendidikan, yang pada gilirannya dijadikan sarana untuk integrasi sistem nasional yang hakekatnya adalah kemajuan dan kesatuan. Sebagaimana telah banyak dikemukakan oleh para pakar di bidang pendidikan, bahwa pendidikan itu ada pendidikan sentral (pusat) dan pendidikan periferi.
Penulis adalah dosen tetap Jurusan Tarbiyah STAIN Samarinda.
Yang disebut pendidikan sentral, pada dasarnya berfokus pada pembentukan hati nurani yang mengutamakan watak, akhlak dan pribadi yang bertanggung jawab dalam hal ini kehidupan moral, sosial dan religius manusia dewasa dalam arti yang hakiki.Membantu anak dalam perkembangannya menuju kedewasaan demikian itulah tujuan pendidikan yang pokok. Itulah pula yang menjadi “fitrah” dan “panggilan” setiap orang tua. Maka dalam lingkungan keluargalah dikatakan terjadi proses pendidikan yang sentral/hakiki. Oleh sebab itu yang didambakan setiap orang tua arif agar dimiliki anak-anaknya, yaitu kebersihan nurani dan keluhuran pekertinya, menyangkut pendidikan moral atau akhlak dan agama.
Sedang yang dimaksud pendidikan peripheral adalah upaya menuju kedewasaan anak, terutama bertujuan mengenalkan anak dengan kehidupan kultural, menjadikannya insan sosial budaya dan insan masyarakat yang sebaik-baiknya. Meskipun yang satu tidak terpisahkan dari yang lain, namun soal pertama lebih banyak menjadi garapan keluarga, sedangkan yang kedua terutama dilaksanakan di luar lingkungan keluarga, misalnya di lingkungan pendidikan formal dan non formal. Namun tidak berarti kedua bentuk pendidikan akhirnya tidak bermuara juga pada satu titik temu yaitu terbentuknya manusia yang dicita-citakan. Tidak dapat dibayangkan jika pendidikan hanya melahirkan orang-orang yang cerdas, cakap dan terampil tanpa dibarengi dengan iman dan taqwa yang sesuai dengan landasan falsafah bangsa dan Negara kita. B. BEBERAPA PRINSIP DAN PENDEKATAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM
Pendidikan Islam memandang bahwa semua pertumbuhan dan perkembangan anak
didik/terdidik dipengaruhi oleh dua faktor yaitu dari dalam dan faktor dari luar atau faktor dasar dan ajar. Hanya saja menurut petunjuk hadits, dinyatakan bahwa pengaruh faktor ekstern atau faktor dari luar itu lebih digambarkan dan diisyaratkan lebih nyata pengaruhnya.
طرةي فأب واه ي هودانيهي أو عن أبي هري رةأن رسول اللهي صلى الله عليهي وسلم قال كل مولود يولد على الفيرانيهي …ي نص
Artinya : “Tiap anak dilahirkan bersih (suci), maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan
dia Yahudi, Nasrani….
Hadist ini memberikan isyarat dengan jelas bahwa pengaruh lingkungan keluarga adalah besar sekali, meskipun dalam batas ia akan dapat menggantikan fitrah terdidik. Dalam pendidikan, terdidik pada umumnya dan remaja pada khususnya, kita harus bersikap realistis, artinya mengakui adanya dua pengaruh tersebut dan mengakui adanya sistem pembinaan yang terus menerus mulai dari kanak-kanak hingga mereka dewasa dan meninggal dunia. Kontinuitas dalam pendidikan ini mutlak diperlukan karena merupakan penjabaran nyata dari konsep pendidikan Islam, yakni “Min al-Wiladati Hatta al-Wafati”, tidak dapat diragukan lagi. Jelaslah di sini bahwa dalam ajaran Islam sebenarnya telah ada konsepsi pendidikan seumur hidup ini, sebelum badan PBB UNESCO menetapkan konsep pendidikan berlangsung seumur hidup atau “Life Long Education”. Di mana-mana memperhatikan konsepsi ini sejak terbitnya buku “An Introduction To Life Long Education” tulisan Paul Lengrand yang diterbitkan pada tahun 1970 yang kemudian dicanangkan oleh UNESCO pada tahun 1971.1 Konsepsi pendidikan seumur hidup ini dalam pendidikan Islam dikenal dengan konsepsi pendidikan “Min al-Mahdi Ila al-Lahdi” atau dari lahir hingga meninggal dunia. Dua macam istilah itu bersumber dari suatu ungkapan popular dalam Islam :
اطلبوالعلم من املهد اىل للحد Artinya : “Tuntutlah ilmu (mulai) dari ayunan hingga ke liang lahad”
Adapun prinsip-prinsip dalam pendidikan Islam antara lain adalah :
a. Pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk kualitas manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
b. Pendidikan Islam selalu berorientasi ke masa depan dan kepada kepentingan si terdidik.
c. Pendidikan Islam berfungsi untuk meningkatkan martabat hidup manusia untuk hidup menurut petunjuk Allah sesuai dengan kodratnya.
d. Pendidikan Islam berlangsung seumur hidup dan merupakan bagian dari kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.
e. Pendidikan Islam memandang manusia sebagai makhluk monodualistik, dan pendidikan Islam memandang tidak ada dikotomi dalam ilmu pengetahuan agama serta tidak ada dikotomi antara urusan duniawi dan ukhrawi.
Atas dasar prinsip-prinsip tersebut dan disesuaikan dengan masalah-masalah yang muncul dengan asumsi tentang pendidikan Islam, dapatlah dibangun berbagai asumsi tentang inovasi Sistem Pendidikan Nasional.
1 Abu Tauhied, Konsepsi Pendidikan Seumur Hidup (Live Long Education) dan Beberapa Faktor yang
Berkaitan dengannya, ( T.tp; tnp, 1971), hal. 16.
Sedangkan pendidikan dalam pendidikan Islam itu adalah pendekatan integral. Sedangkan pendekatan dalam pendidikan dengan sistem parsial atau monolitik itu bukan Islam. Pendekatan yang integral tersebut mengembangkan pendidikan Islam kepada asas sebenarnya, yakni membentuk dasar-dasar kepribadian muslim. Telah disebutkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 208, Allah berfirman :
الشيطان إنه لكم عدو مبين يا أي ها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ول ت تبعوا خطوات Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman masukklah kalian ke dalam Islam secara
utuh/keseluruhan, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah Syaitan, sesungguhnya Syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.
Ini mengandung pengertian bahwa sebenarnya agama itu, yang ajaran pokoknya adalah moral, bukan hanya merupakan salah satu sektor kehidupan saja, tetapi merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan, bahkan dasar esensial dari kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu pendidikan agama, yang dalam hal ini pendidikan moral perlu
mendapatkan dukungan dan ada jalinan yang erat dari semua bentuk dan lingkungan
pendidikan lainnya. Misalnya dalam penanaman suatu moral seharusnya tidak terjadi
kontradiksi atau peradoksa antara keluarga, sekolah dan suatu masyarakat. Contoh yang lain
adalah guru IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) dapat menghubungkan pelajarannya dengan
kebesaran Allah. Demikian juga guru-guru lainnya, guru IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial),
Guru Ilmu Ekonomi dan lain-lain, minimal tidak mempertentangkannya. Orang tua dan guru
dapat memanfaatkan suatu keadaan tertentu misalnya adanya musibah banjir, juga musibah
kebakaran, untuk menumbuhkan rasa solidaritas sosial kepada anak-anak/murid-muridnya
dan sekaligus rasa keagamaan.
C. BEBERAPA DINAMIKA PSIKOLOGI REMAJA
Berbicara masalah remaja, khususnya pengembangan “Moral Remaja Indonesia dalam Pendidikan Islam”, sebenarnya memerlukan tinjauan dari beberapa aspek atau faktor baik faktor Tarbiyah Islamiyah dan kebudayaan Bangsa Indonesia sendiri maupun aspek-aspek lainnya seperti Sosial, Ekonomi, Politik, dan lain-lainnya. Keseluruhan aspek-aspek tersebut sangat mempengaruhi eksistensi para remaja. Remaja adalah suatu masa dari unsur manusia yang paling banyak mengalami perubahan sehingga membawanya pindah dari masa anak-anak menuju dewasa. Karena itu pada masa remaja ini terdapat banyak kegoncangan pada diri remaja itu.2 Perubahan yang terjadi meliputi aspek rohani, perasaan, pikiran dan sosial yang akan membawa kepada berbagai masalah, tekanan dan goncangan. Kegoncangan jiwa akan banyak terpengaruh oleh situasi kehidupan keluarga dan lingkungan sosial, yang pada gilirannya akan
2 Sofyan S. Willis, Problem Remaja dan Pemecahannya, (Bandung, Angkasa, 1981), hal. 19.
mengakibatkan terjadinya remaja tidak mempunyai persiapan jiwa yang cukup untuk menghadapi segala persoalan yang timbul. Perubahan dan pembaharuan pola kehidupan yang sedang berlangsung di sekitarnya secara terus menerus akan membawa akibat-akibat sosial tertentu, antara lain timbulnya rangsangan terhadap tata nilai yang salah di samping tidak dikehendaki juga akan berbahaya. Namun suatu kenyataan bahwa suatu kelompok yang paling peka terhadap rangsangan tersebut adalah kaum remaja atau kawula muda.Oleh karena itu kawula muda perlu diajak untuk mengerti tata nilai yang ada dan harus diketahui yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal lebih luas sekarang ini ialah remaja harus tahu akan jati diri bangsa Indonesia. Masa muda memanglah unik, sebab pada diri mereka itu penuh dinamika yang sangat potensial, sehingga akan mampu melukis sketsa dan ukiran dunia ini dalam aneka ragam bentuk formalnya. Oleh karena itu apapun keadaan dunia pendidikan di Indonesia dewasa ini, bukanlah hambatan. Memang segala sesuatu terikat dengan dimensi dan yang pasti kita tidak menghendaki kematangan remaja karbitan. Untuk itu pembangunan kualitas sikap mental berupa seperangkat keimanan, kemurnian, niat dan idealisme kawula muda perlu dicanangkan yang mampu sedalam lubuk hati sanubari kepribadiannya. Di antara beberapa dinamika psikologik remaja itu adalah : 1. Para remaja potensial sekali memegangi keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
dengan sepenuh tanggung jawabnya. Kawula muda itu secara asli memeluk agama dengan sangat kuat. Dalam dinamika hidupnya membiasakan memacu diri pada perintah agama. Kalaupun ada penyimpangan, hal itu terjadi justru karena referensi yang diperoleh dari keterangan orang dewasa sekelilingnya.
2. Landasan hidup remaja lebih terangsang oleh kenikmatan sebagai prinsipnya, temperamen mereka selalu mengejar kenikmatan. Namun dari rasa syukur asai, justru membuat mereka tidak kenal putus asa dalam kehidupan mereka yang murni.
3. Mereka remaja mempunyai naluri “Satu Inci kebangatan (keakraban) sama dengan setengah kehidupan”. 3Mereka dalam hubungan sosial baik dalam keluarga, teman sebaya, maupun masyarakat selalu mencari titik temu kehangatannya. Hal itu dilakukan dalam hubungan antar insan karena dilandasi oleh prinsip asasi tersebut. Sehingga mereka senantiasa getol menciptakan kemesraan diantara mereka agar terjauh dari kekurangan vitamin K (kesepian).
4. Mendekati puas itu memang tidak puas, tetapi kepuasan mutlak justru berbahaya sekali. Mereka para remaja selalu tidak puas, atau mungkin hanya mendekati puas sehingga mereka selalu terdorong untuk berlomba maju. Etos kerja mereka, sangat tinggi karena dilandasi oleh filosifi “tidak mau merasa puas mutlak”.
5. Para remaja tidak takut menghadapi kegagalan karena mereka beranggapan sukses dapat dibangun dari kegagalan.
6. Bahtera dahsyat adalah milik kawula remaja. Mereka tidak takut menghadapai tantangan. Tantangan bagi mereka diterima dengan lapang sebagai pengalaman yang bernilai positif bagi peningkatan produktifitas mereka.
7. Mereka berusaha mengenali daya angkut mereka. Dalam dinamika kehidupan mereka, mereka selalu meraba-raba sejauh mana daya kemampuan dirinya dan selalu berusaha
3 Asip F. Hadipranata, Remaja Dalam Pendidikan Nasional, Makalah. 1990
mengembangkan dan menyelaraskan daya angkut yang sesuai dengan kekuatan yang dimilikinya.
D. PROBLEMA PENGEMBANGAN MORAL REMAJA
Kita bangsa Indonesia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya perlu bersyukur bahwa arah tujuan pendidikan Nasional telah digariskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 20 Tahun 2003 Bab II pasal 3 yang berbunyi : “ Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”4 Dari rumusan tersebut dapat dikatakan bahwa yang menyangkut moral agama adalah iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meskipun sikap dan sifat yang lainpun tidak dapat dilepaskan darinya. Itu berarti bahwa sasaran utama Pendidikan Nasional adalah tumbuh dan terbinanya iman dan taqwa pada anak/remaja dan bersama-sama dengan bentuk pendidikan lainnya membina dan menumbuhkan sifat dan sikap yang lainnya itu. Titik tolak kepribadian remaja adalah iman atau keyakinan, dan kemudian diperkuat oleh pengetahuan dan pemahanan agama agar dapat melaksanakan dengan benar sesuai dengan ketentuan sebagai penjabaran ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.Taqwa berarti penyerahan dan kepatuhann terhadap semua perintah atas dasar rasa ketergantungan. Masa remaja adalah masa transisi dan secara psikologis sangat problematis. Masa ini memungkinkan mereka berada dalam “anomi”, keadaan tanpa norma maupun orientasi mendua.5 Dalam keadaan demikian sering muncul perilaku penyimpangan atau kecenderungan malakukan pelanggaran. Anomi muncul akibat keanekaragaman dan kekaburan norma. Misalnya, norma yang ditanamkan dalam keluarga bertentangan dalam norma yang diskusikan di luar lingkungan keluarga. Generasi remaja ini akan merupakan generasi konflik. Di satu sisi orang tuanya melarang tetapi di televisi “Kok Boleh”. Generasi di bawah mereka akan merupakan “Generasi serba boleh” sedangkan masyarakat yang ia harapkan mampu memberi jawaban juga berada dalam keadaan transisi dan tak mampu memberikan apa yang diharapkan remaja. Dalam keadan bingung inilah mereka berusaha mencari pegangan norma lain yang bisa mengisi kekosongan tersebut. Kesempatan yang memberi peluang pada penyimpangan dan pelanggaran akibat kesalahan pegangan. Adapun mengenai orientasi mendua, adalah orientasi yang bertumpu pada harapan orang tua, masyarakat dan bangsa, yang sering bertentangan dengan keterikatan serta loyalitas terhadap kawan sebaya, apakan itu di lingkungan belajar (sekolah) atau di luar sekolah. Kondisi bimbang yang dialami remaja ini menyebabkan mereka melahap semua informasi tanpa seleksi. Dengan demikian mereka adalah kelompok potensial yang mudah dipengaruhi
4 http://www.inherent-dikti.net/files/sisdiknas.pdf, akses tanggal 5 Mei 2012 5.Machbub Masduqi, Pembinaan Moral bagi Generasi Muda dalam rangka Ketahanan Nasional, Pidato Dies
Natalis ke VI IAIN Wali Songo, 1976.
media manapun bentuknya.Keadaan bimbang akibat orientasi mendua juga sering menyebabkan remaja berbuat hal-hal yang sifatnya nekat. Hal ini antara lain akibat dari pertentangan nilai antara kawan sebaya dengan pola asuh dan pendidikan keluarga. Dewasa ini banyak tersedia pilihan isi informasi, sementra remaja merupakan periode peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa ditandai beberapa ciri, 1. Keinginan memenuhi menjalankan identitas diri. 2. Kemampuan melepaskan diri dari ketergantungan pada orang tua. 3. Kebutuhan memperoleh akseptabilitas ditengah sesama remaja.
Ciri – ciri tersebut menyebabkan kecenderungan remaja melahap begitu saja arus informasi yang serasi dengan selera dan keinginan mereka. Di samping juga para orang tua yang seharusnya berfungsi sebagai penepis informasi atau pemberi rekomendasi terhadap pesan-pesan yang diterima, tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Dalam hal ini sebenarnya orang tua memberikan pendidikan disiplin sejak dini, di mana seharusnya remaja/kawula muda mempunyai rasa kecintaan dan sekaligus juga rasa takut atas kebesaran- Nya. Kecintaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kemurahan dan kasih saying-Nya kepada manusia (Rahman dan Rahim), dan takut kepada-Nya karena bila manusia berdosa murka-Nya pun amat besar (di samping surga yang didambakan oleh umat beragama sebagai pahala tertinggi, yang ada neraka, hukuman yang paling ditakuti oleh umat manusia).Uraian di atas membawa konsekuensi bahwa pendidikan moral agama hendaklah pertama diarahkan pada ranah efektif, dan baru kemudian kognitif, dan psikomotorik sesuai dengan tahap-tahap perkembangan jiwa anak sehingga akhirnya tercapai tahap kebulatan dan keutuhan pribadi “Insan Kamil”. Menurut pendidikan Islam semua anak itu dilahirkan dalam keadaan “Fitrah”. Fitrah artinya berpotensi baik. Dalam hadits sebagaimana diuraikan pada bagian awal dari tulisan ini Al Ghazali memberikan komentarnya sebagai berikut :
“Sesungguhnya seorang anak itu, dengan jauharnya diciptakan Allah dapat menerima kebaikan dan keburukan keduanya.Dan hanya kedua orang tuanya yang dapat menjadikan anak itu cenderung pada salah satu pihak “.6
Dengan demikian Islam bersikap optimis dalam pendidikan. Namun demikian karena masalah iman seseorang itu merupakan petunjuk langsung dari Tuhan yang hanya diberikan kepada orang-orang yang dikehendakiNya, maka optimisme pendidikan Islam itu tidaklah mutlak. Maka sambil mendidik dan memperkembangkan moral remaja, wajarlah kiranya bila kita sertai dengan doa semoga upaya kita berhasil. Berbagai problema yang sering dihadapi remaja, ada problema yang berdiri sendiri tetapi lebih banyak merupakan campuran dari bebrapa problem sekaligus. Di antara problema remaja itu antara lain adalah kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang tua. Problema ini paling sering didapat dan kerap kali merupakan problema yang mendasari problema-problema lainnya. Gejala kesulitan hubungan dengan orang tua bisa berupa
6 Zainuddin, Seluk Beluk Pendidikan dari Al-Ghazali; (Bumi Aksara, Jakarta 1991), hal. 65.
kesulitan komunikasi (sukar untuk saling mengerti). Remaja suka membantah kemauan orang tua, remaja sama sekali tidak mau bicara dengan orang tua. Adapun faktor penyebab dari kesulitan komunikasi dengan orang tua ini antara lain : 1. Perbedaan norma yang dianut oleh orang tua dan yang dianut oleh remaja. Dalam hal ini
orang tua menggunakan norma-norma lama yang berlaku bagi diri mereka sendiri semasa mereka remaja. Yang tentu saja berlainan dengan kondisi remaja masa kini.
2. Tidak adanya konsistensi kriteria yang diberlakukan dalam keluarga kadang-kadang seorang ibu, karena kasih sayang pada putranya membiarkan putranya melakukan hal-hal yang dilarang oleh ayahnya dan sebaliknya. Inkonsistensi itu dapat juga terjadi pada orang tua yang sama, misalnya seorang ayah melarang putranya merokok tetapi dia sendiri perokok yang kuat. Inkonsistensi dalam penerapan kriteria akan mengganggu perkembangan moral anak/remaja di samping juga membawa kemerosotan wibawa orang tua.
3. Cara mendidik orang tua yang kurang benar misalnya terlalu otoriter atau terlalu liberal. Problema kesulitan dalam hubungan dengan orang tua adalah merupakan problema yang paling sering didapat dan kerap kali merupakan problema inti yang mendasari problema-problema lainnya. Kiranya perlu didasari bahwa kualitas hubungan orang tua dan akan adalah sangat penting dan lebih pada sekedar kuantitas (frekuensi). Kesibukan orang tua yang memungkinkannya sedikitnya waktu untuk bertemu antara anak dan orang tua, tidak akan membawa kepada kerumitan “hubungan yang hangat” itu sudah terjadi. Orang tua diharapkan bisa memahami kekurangan anak, demikian juga harus terbuka menghadapi kenyataan akan kekurangannya sendiri.
Untuk pengembangan moral remaja, dasar pembentukannya harus diberikan sedini mungkin. Nabi Muhammad SAW bersabda :
ها وهم أب ناء عشر وف رقو ن هم في مروا أولدكم بالصلة وهم أب ناء سبع سنين واضربوهم علي ا ب ي المضاجع
Artinya : “ Suruhlah anak-anakmu menjalankan ibadah sholat disaat mereka berumur tujuh
tahun, dan tegurlah (bilamana perlu diberikan “hukuman”) jika sudah berumur sepuluh tahun mereka enggan (tidka berdisiplin) menjalankan ibadah sholat. Dan pisahkan tempat tidur mereka.
Jadi justru pada saat orang tua masih banyak berperan dan mempunyai otoritas pada anak itulah masa yang paling tepat untuk penanaman pembiasaan dan kedisplinan. Disiplin pada hakekatnya adalah penyesuaian antara tata laku dan tata pikir seseorang atau kelompok dengan suatu peraturan atau nilai-nilai yang diberlakukan. Disiplin tidak biasa tumbuh dan berkembang tanpa dibina dan rekayasa. Apalagi pada tahap prekonvensional itu anak sudah dibiasakan dengan dasar moral yang baik dan disiplin yang baik, maka perkembangan positif dapat diharapkan. Dengan catatan bahwa apa yang diberitahukan pada anak bukanlah hanya
bersifat informatif tetapi dari pada itu adalah “keteladanan”, karena dalam pengembangan moral itu penciptaan situasi lebih penting dari pada pemberian informasi. K.H. Hamin Jazuli seorang da’i yang popular di Jawa Timur yang biasa dipanggil Gus Mik, menyatakan bahwa dalam era informasi dan era globalisasi seperti sekarang ini dalam rangka penanaman nilai moral bagi anak-anaknya, orang tua harus menguasai tiga “bahasa” yakni disamping bahasa kata yang lebih penting lagi bahasa gaul dan bahasa hati. Mendidik moral anak, lanjut gus Mik, tidak hanya menggunakan bahasa kata, tegur sapa, perintah dan larangan yang bersifat verbalistis, melainkan juga disertai bahasa gaul yaitu contoh keteladanan dan bahasa hati yang berarti ikhlas dan terbuka. 7
E. PENUTUP
Untuk pengembangan moral remaja, preventif dan kuratif, alternatif yang kiranya tetap perlu dikembangkan yaitu : 1. Mengaktifkan kembali tugas dan fungsi keluarga sebagai lembaga pendidikan yang
pertama dan utama. Keluarga merupakan wadah untuk menempa kepribadian anak dengan penanaman nilai (afektif) pendidikan moral, sehingga sejak dini pada diri anak tertanam nilai-nilai moral yang akan memandu dalam bersikapn dan berperilaku.
2. Penegakan kedisiplinan dan hukum, karena disiplin dan kepastian hukum akan berpengaruh besar bagi remaja dalam proses pengukuhan identitas dirinya. Kedisplinan akan tertanam, jika keseharian remaja terpola dengan sikap disiplin.
7 Jawa Pos, 2 Pebruari 1992.
BIBLIOGRAFI
Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Himpunan Peraturan Perundang-undangan Sistem Pendidikan Nasional, tahun 1991/1992
Gunarsa, Singgih D., Singgih D. Gunarsa, Anak dan Remaja, Psikologi Perkembangan, Cert. ke-5, PT bpk gunungmulia, 1989
Hadipranata, Asip F., Remaja dalam Pendidikan Nasional, Makalah, 1990 Kartono, Kartini., Peranan Keluarga Memandu Anak Seri Psikologi Terapan 1, Rajawali Jakarta,
1985. Masduqi, Mchbub, Pembinaan Moral bagi Generasi Muda dalam Rangka Ketahanan Nasional,
Pidato Dies Natalis ke VI IAIN Wali Songo, 1976. Soekanto, Soerjono., Sosiologi Keluarga tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak, Rineka Cipta,
1990. Syekh ga el haq Ali Gad el Haq, Mengasuh Anak menurut Ajaran Islam, Litbang Depertemen
Agama, Jakarta, 1986. Tauhied, Abu., Konsepsi Pendidikan Seumur Hidup (Life Long Education) dan beberapa faktor yang
berkaitan dengannya, halaman 16. Willis, Sofyan S., Problema Remaja dan Pemecahannya, Angkasa, Bandung, 1981 Zainuddin, Seluk Beluk Pendidikan dari Al-Ghazali, Bumi Aksara, Jakarta 1991
ASPEK PENGEMBANGAN PESERTA DIDIK
(KOGNITIF, AFEKTIF, PSIKOMOTORIK)
Syeh Hawib Hamzah
Abstract ; Education is the most important thing to students as guidance to go through the life. In this case, education process has to be designed specifically in terms of students’ development of cognitive, affective, and psychomotor competence. These three aspects need to be developed comprehensively so that academic, social, and creative competence of students can be maximally actualized. Key Words : Pengembangan, Kognitif, Afektif, Psikomotorik
A. PENDAHULUAN
Berbicara tentang peserta didik tentu tidak terlepas adanya pendidik sebagai satu komponen dalam kegiatan proses pengembangan potensi peserta didik untuk mau menerima perubahan. Fungsi utama pendidik adalah bagaimana membuat rancang bangun, sedangkan peserta didik sebagai penerima rancang bangun menetukan pilihan dari apa yang datang dari pendidik itu sendiri.
Hal ini mendorong akan adanya pengembangan yang perlu dipahami dari setiap peserta didik oleh pihak yang berkompeten yaitu pendidik. Jabatan guru telah hadir cukup lama di negeri ini. Guru mendapat pengakuan terhormat dengan motto “pahlawan tanpa jasa”, artinya menjadi sosok pribadi guru sangat terhormat. Guru adalah agen pembawa perubahan dan sekaligus pengembang amanah yang mulia. Sosok guru bukan sekedar guru tapi tokoh yang digugu dan ditiru1. Pembelajaran yang terjadi pada sekolah atau madrasah yang diterima langsung oleh peserta didik dirasakan dominan mengarah pada pengajaran kognitif, terkesan sekedar penyampaian materi pelajaran (transfer of knowledge ) mengabaikan aspek afektif akibatnya pembelajaran menjadi kurus lagi kering akan nilai-nilai pendidikan secara kaffah (menyeluruh).
Peserta didik tidak memperoleh proses pendidikan yang relevan dengan fakta-fakta kehidupan sehari-hari. Survei membuktikan keberhasilan pendidikan pada 10 tahun terakhir ini (Orde Reformasi) hanya diukur dari keunggulan ranah
Penulis adalah dosen tetap pada Jurusan Tarbiyah STAIN Samarinda, doktor lulusan
pasacasarjana UIN Alauddin Makassar. 1 Digugu dan ditiru adalah bahasa Jawa yang mempunyai arti dipercaya dan dijadikan
panutan/ suri tauladan.
kognitif dan nyaris tertindas dan tidak menyentuh ranah afektif serta ranah psikomotorik (perbuatan). Pada hal untuk memperoleh keberhasilan yang tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, ke tiga ranah itu tidak bisa terpisahkan. Peserta didik punya hak untuk memperoleh ilmu pengetahuan, perilaku, akhlakul karimah dan keterampilan yang memadai.
Menjadi keprihatinan bersama bertumpuh kepada apa seharusnya peserta didik yang diharapkan dari guru dan sebaliknya guru dituntut menuntut Peserta didik untuk mengenal ke tiga aspek tersebut. Proses evaluasi sering kali pihak guru memandang proses pengukuran sesaat dan parsial sehingga hasil belajar yang tampak tidak sesuai dengan fakta atau kemampuan peserta didik. Menyikapi dengan bijak apa yang menjadi penomena pada latar belakang tersebut maka yang menjadi kajian penulis dititikberatkan pada belajar sebagai suatu aspek perubahan, faktor yang mempengaruhi belajar, peserta didik sebagai makhluk belajar, penilaian hasil belajar pada aspek kompetensi.
B. BELAJAR SEBAGAI KEBUTUHAN UNTUK PERUBAHAN
Banyak orang yang beranggapan bahwa yang dimaksud dengan belajar adalah mencari ilmu atau menuntut ilmu. Adalagi yang secara khusus mengartikan belajar. Banyak yang mempertanyakan apakah dengan belajar semacam itu orang menjadi bertumbuh dan berkembang? Banyak macam kegiatan yang dapat digolongkan kepada belajar mencari arti sebuah kata dalam kamus, mengingat, menghafal puisi, membaca pelajaran, menalaah ulang pelajaran yag diperoleh dari guru di sekolah, mempersiapkan pelajaran yang akan dipelajari untuk minggu depan, membuat ringkasan, atau resume, berdiskusi dengan teman, mengenai bagian pelajaran yang telah diterapkan guru di sekolah, memperhatikan alam dan lingkungan.
Tingkah laku belajar yang dilakukan di atas, merupakan kegiatan harian, sehingga lama kelamaan dalam dirinya akan terjadi suatu perubahan dalam diri orang yang belajar. Misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dari bodoh menjadi pandai yang semula tidak bisa mengerjakan suatu pekerjaan, akhirnya bisa mengerjakan atau bahkan mampu memberi petunjuk kepada temannya. Sebelum belajar ia tidak bisa membaca, lalu mampu menulis dan mengarang. Semua yang terjadi itu telah merubah keadaan jiwa dan motorik peserta didik, sehingga ia memiliki keadaan yang jauh berbeda dengan keadaan sebelum belajar. Belajar menyebabkan terjadinya perubahan pada peserta didik.
Dari kegiatan atau tingkah laku belajar di atas dapat ditelaah bahwa ada kegiatan psikis dan pisik yang saling bekerja sama secara terpadu dan komprehensip dan integral. Sebagai contoh dapat dipaparkan, bila seseorang membaca artikel baru, maka jiwanya setuju kepada simbol bahasa dalam bentuk tulisan dan panca indera matanya menelusuri kata demi kata serta kalimat demi
kalimat. Setelah ia selesai membaca artikel tersebut, dalam dirinya terjadi perubahan yaitu bertambahnya wawasan, kepercayaan diri, gembira, senang, dan punya nilai emosional, lahirlah integritas, kejujuran, komitmen, visi, kreativitas, kepekaan sosial, kebijaksanaan, keadilan, kepercayaan dan penguasaan diri dan makin tinggi minat untuk mempelajari buku-buku dan sebagainya.
Dalam psikologi anak dikatakan bahwa hal-hal yang tidak sama dengan sebelum belajar disebut perubahan atau modification. Perubahan ini secara psikologis menetap pada orang yang belajar, karena dalam dirinya telah terbentuk suatu habit atau kebiasaan tertentu bila berhadapan dengan sesuatu yang hendak dipelajari. Dalam psikologi belajar hal ini disebut stimulus (rangsangan) dari luar diri mengenai dirinya dan bagian-bagian tubuhnya, kemudian merespon terhadap stimulus tadi maka terjadilah suatu proses psikis dan fisis dalam dirinya. Hasil dari proses ini terjadilah berbagai kegiatan dalam otaknya misalnya mengasosiasikan, membedakan, menyerap yang dibantu oleh sistem persyarafan.2
Atas dasar ciri perubahan terjadi pada diri orang yang belajar maka semua defenisi belajar yang dikemukakan oleh ahli psikologi belajar menjadikan perubahan ini sentral dari defenisinya. Maka terdapatlah berbagai definisi belajar yang dikemukakan para ahli seperti ; 1. E.R. Hilgard mendefinikan belajar sebagai berikut; learning is the process by
witch an activity orginates or is changed through training prosedure (wheter in the laboratory or in natural environment) as distringuished from changes by factor not atributtable to training.3 Belajar adalah suatu proses aktivitas yang awal atau selesai melakukan pelatihan (apakah itu dilaboratorium atau di lingkungan alam) sehingga dapat dibedakan perubahan yang terjadi karena faktor yang bukan diakibatkan oleh pelatihan).
2. Cronbach dalam bukunya yang berjudul “Educational Psychology” mendefinisikan ; learning is shown by change in behavior as a result of experince.4 Belajar adalah terjadinya perubahan tingkah laku diperoleh dari pengalaman.
3. Howard L Kingsley mendefenisikan bahwa “learning is the proces by which behavior (in the boarder sense) is originated or changed through pactice of training5 Belajar adalah proses dimana tingkah laku (dalam arti luas) ditimbulkan atau diubah melalui peraktek atau latihan.
2 Aminuddin Rasyad, Teori Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Uhamka Presss,2003 ), hal.
28 3 E.R. Hilgard, Teoritis of Learning, (New York Appleton Century Crofts, 1948), hal. 4 4 Lee J. Cronbach, EducationalFfsicology, New Harcourt, Grace, 1954), hal. 47 5 Howard L. Kingsley & Ralp Garry, The Nature and Condition of Learning, N.J. Practice
Hall, Inc, Engliwood Clifts, 1957), hal. 12
4. Laster D. Crow & Alice Crow mendefenisikan” Learning is the acuquisition of habit, knowledge and attitudes”6 Belajar adalah terjadinya perubahan terhadap kebiasaan, ilmu pengetahuan dan sikap.
Dari defenisi yang dikemukakan para ahli di atas dapatlah diambil hal-hal
pokok dalam belajar sebagai berikut; a. Bahwa belajar itu memabwa perubahan (arti behavior changes dan knowledge) b. Perubahan itu pada pokoknya akan menimbulkan kecakapan baru c. Bahwa perubahan itu terjadi karena usaha yang disengaja
Adapun secara lebih rinci bahwa belajar membawa perubahan pada tiga aspek seperti yang dikemukaan Bloom dan Krath Wohl yaitu ;7 1. Kognitif
Kognitif terdiri 6 kata yaitu ; a. Pengetahuan (mengingat, menghafal) b. Pemahaman (menginterpretasikan) c. Aplikasi (menggunakan konsep, memecahkan masalah) d. Analisis (menjabarkan suatu konsep) e. Sintesis (menggabungkan nilai, metode, ide dll) f. Evaluasi (membagikan nilai, ide, metode dll)
2. Afektif Afektif terdiri dari 5 tingkatan;
a. Pengenalan (ingin menerima,sadar akan adanya sesuatu) b. Meresepon (aktif berpartisipasi) c. Penghargaan (menerima nilai-nilai, setia kepada nilai-nilai) d. Pengorganisasian (menghubung-hungkan nilai-nilai yang dipercayai) e. Pengamalan (menjadikan nilai-nilai sebagai bagian dari pola hidup)
3. Psikomotorik
Psikomotorik terdri dari 5 tingkatan ; a. Peniruan (menirukan gerak) b. Penggunaan (menggunakan konsep untuk melakukan gerak) c. Ketapatan (melakaukan gerak dengan benar) d. Perangkaian (melakaukan beberapa gerakan sekaligus dengan benar) e. Naturalisasi (melakukan gerak secara wajar)
6 Laster D. Crow & Alice Crow, Educational Fsicology Human Development and learning, tt,
hal. 24 7Hamzah B. Uno, Orientasi baru dalam Psikologi Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),
hal. 14
C. FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI BELAJAR
Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi belajar itu banyak sekali macamnya. Faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
1. Faktor-faktor yang berasal dari luar peserta didik yakni faktor-faktor non sosial dan sosial,
2. Faktor-faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik yakni faktor-faktor fisiologis dan psikologis.8 Dari beberapa faktor dalam belajar tersebut dapat di jelaskan sebagai
berikut: 1. Faktor-faktor non sosial dalam belajar
Kelompok faktor ini boleh dikatakan juga tak terbilang jumlahnya seperti keadaan udara, suhu, cuaca, waktu (pagi, siang, malam), tempat (letaknya, pergedungannya), alat-alat yang dipakai untuk belajar (seperti alat tulis menulis, buku-buku, alat peraga dan sebagainya yang biasa disebut alat pelajaran.
Semua faktor-faktor yang telah disebutkan di atas dan yang belum disebutkan harus diatur sedemikian rupa sehingga proses belajar berjalan dengan baik dan maksimal. Letak tempat belajar harus jauh dari kebisingan. Demikian pula alat-alat pelajaran harus disesuaikan dengan pertimbangan didaktis, psikologis dan paedagogik
2. Faktor-faktor sosial dalam belajar
Yang dimaksud faktor-faktor sosial disini adalah faktor-faktor manusia (sesama manusia tersebut mengganggu konsentrasi belajar misalnya kalu satu kelas murid sedang mengerjakan ujian, lalu terdengar anak-anak lain bercakap-cakap di samping kelas, sehingga perhatian tidak dapa ditujukan kepada hal yang dipelajari.
3. Faktor fisiologis
Faktor fisiologis adalah berkenaan dengan keadaan jasmani peserta didik. Jasmani yang segar akan lain mpengaruhnya dengan jasmnai yang kurang segar. Keadaan jasmani yang lelah lain pengaruhnya dari pada yang tidak lelah. Bagi kondisi jasmani yang sakit, tidak segar, mengantuk akan membuyarkan konsentrasi belajar bahkan tidak mampu menyerap materi pelajaran. Oleh larena itu peserta didik harus dikondisikan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran jasmani dengan memakan makanan yang bergizi dan berolah raga yang teratur
. 4. Faktor –faktor Psikologis dalam belajar
8 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Perss, 1987), hal. 249
Faktor psikologis ini berkaitan dengan kejiwaan peserta didik, intelegensi, sedih, frustasi, putus asa dan lain-lain. Factor ini juga sangat berpengaruh pada proses belajar. Peserta didik yang intelegensinya dibawah normal akan sulit untuk mengingat pelajaran. Kondisi psikis seperti sedih, frustasi, putus asa jika dialami peserta didik maka konsentrasi belajarnya akan buyar dan perhatiannyapun tidak akan terpokus pada pelajaran. Untuk itu pendidik harus tanggap dengan kondisi psikis peserta didik dan berupaya untuk mengatasinya jika terjadi problem psikis pada peserta didik tersebut.
D. PESERTA DIDIK SEBAGAI MAKHLUK BELAJAR
Alquran memandang bahwa semua manusia dapat diajar. Ini terbukti dari seruan Alquran yang pada dasarnya untuk seluruh umat manusia dengan ungkapan (Yā Ayyuhannās) tanpa mengedepankan kelompok tertentu. Adapun keunikan gaya dan metodologinya, seolah-olah berbeda dengan metode ilmiah adalah merupakan unsur kemukjizatannya, dimana seruannya disesuaikan dengan kondisi sosial, intelektual dan kultural masing-masing audiensnya9.
Manusia (peserta didik) menerima pelajaran dari Tuhan tentang berbagai pengetahuan yang menyangkut ibadah, akidah, tauhid, akhlak, muamalah dan lain-lain. Tuhan di sini berperan sebagai pendidik yang Maha luas ilmu-Nya (al-Alīm) yang mengajari manusia apa yang tidak diketahui. Manusia menjadi peserta didik-Nya, akan tetapi Tuhan tidak secara langsung berdiri dihadapan peserta didik-Nya dalam menyampaikan pengatahuan melainkan melalui perantara yaitu Alquran.
Sebagai makhluk belajar, manusia belajar kepada sumber-sumber belajar. Sumber belajar dalam pendidikan Islam menurut Azyumardi Azra yaitu: 1) al-Quran yang merupakan sumber pertama dan utama yang dikembangkan menjadi teori, 2) Sunnah Nabi, 3) Fatwa sahabat yang masih menyaksikan perilaku nabi secara langsung, 4) kemaslahatan yang membawa mamfaat, 5) nilai adat istiadat yang berasal dari nilai-nilai budaya masyarakat yang positif, 6) pemikiran para Filosof dan intelektual muslim yang representatif.10
Oleh karena manusia sebagai pelaksana pendidikan, juga sebagai makhluk yang memiliki potensi untuk diberikan pendidikan, maka perlu adanya proses pembelajaran. Dengan melalui proses pembelajaran diharapkan peserta didik mengalami perubahan yang mewujudkan kecakapan baru di antaranya:
9 Muhammad Husin At-Thabathabai, Memahami Esensi al-Quran, Terj. Mahyuddin,
(Jakarta: Lentera, 2000), hal. 39 10 Azyumardi Azra, Esei-Esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos,
1999), hal. 11
a. Kecakapan akademik. Pada tataran ini pendidikan harus dapat memberikan perubahan dan
mengembangkan kemampuan membaca, menulis, memahami, meneliti, memecahkan masalah dan lain-lain. Oleh karena itu pendidikan harus dapat memotivasi kepada peserta didik untuk cinta kepada membaca dan menulis sebagai kunci ilmu pengetahuan. Pengetahuan dimulai dari membaca dan menulis sebagaimana firman Allah dalam Alquran “ Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam (pena)” (QS. 96: 1-5). Dalam ayat yang lain dinyatakan “ Nun, demi qalam, dan apa yang mereka tulis (QS. 68 : 1)”
Dengan demikian ilmu yang diperoleh itu harus ditulis agar dapat langgeng dan dapat dibaca kembali sehingga terhindar dari kelalaian. Hal ini dapat diteladani pada perkataan sahabat nabi Anas bin Malik Al Anshari kepada anak-anaknya” Hai anak-anakku ikatlah ilmu dengan tulisan” dan lebih lanjut dia berkata” kami tidak menganggap suatu ilmu bagi siapa yang tidak menulis ilmunya”11.
Di samping membaca dan menulis pendidikan juga harus memberikan nuansa kepada peserta didik untuk dapat memahami, memperhatikan dan meneliti tanda-tanda kekuasaan Tuhan sebagaimana al-Quran menyatakan” maka tidaklah mereka meperhatikan Onta bagaimana diciptakan dan langit bagaimana ditinggikan? Dan gunung-gunung bagaimana di tegakkan? (QS. 88 : 17-20) dengan demikian kemampuan intelektualnya dapat berkembang sehingga pada gilirannya membawa perubahan kognitif pada peserta didik.
b. Kecakapan Sosial Manusia sebagai makhluk sosial terus mengalami perkembangan.
Perkembangan sosial merupakan kegiatan manusia sejak lahir, dewasa sampai akhir hidupnya akan terus melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan sosialnya yang menyangkut norma-norma dan sosial budaya masyarakatnya.12 Di mana sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa orang lain maka manusia melakukan interaksi antar individu-individu. Allah menyatakan dalam al-Qura`an : Wahai manusia sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal...”(QS. 49 : 13) dalam interaksi dan pergaulan tersebut harus sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat.
11 Muhammad bin Mathar az- Zahroni, Tadwin As-Sunnah an-Nabawiyah wa Totowwiruhu
min al-Quran al-Awwal ila Nihayah al-Quran at-Tasyi al Hijr, Madinah al –Munawwarah: Daar al-Khudari, 1998), hal. 88-89
12 Dja`ali, Psikologi Pendidikan, (Jakarta; Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, 2000), hal. 124
Oleh karena itu peserta didik mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat, dimana diberikan pendidikan akhlak yang sejalan dengan nilai-nilai agama sebab begitu rumit dan banyaknya masalah yang menyangkut manusia sebagai makhluk sosial yang perlu bimbingan agama13.
Islam mengajarkan bagaimana cara bergaul dengan orang lain diantaranya saling bekerja sama dan tolong menolong dalam hal yang baik (QS. : 5 :2), saling menyayangi dan mencintai, hadis nabi mengatakan “ Kau lihat orang mukmin saling menyayangi, saling mencintai dan saling berbuat baik, bagaikan satu tubuh yang apabila ada yang sakit seluruh tubuh turut tidak bisa tidur dan turut merasa sakit (H.R. Buchari).
Dengan diajarkan agama dan nilai-nilai yang baik diharapkan peserta didik memiliki kepribadian, berakhlak mulia sehingga tercipta suatu masyarakat yang harmonis
. c. Kecakapan Berkarya
Manusia sebagai makhluk biologis (basyar) yang dipengaruhi oleh dorongan kodrat alamiahnya seperti makan, minum , bersetubuh, dan lain-lain. Dalam rangka memenuhi kebutuhan makan , minum dengan cara yang halal lagi baik. Untuk itu peserta didik harus dibekali keterampilan. Islam sendiri mengajarkan tentang hal tersebut. Terungkap dalam sebuah hadis ; “ Kewajiban orang tua terhadap anaknya memberi nama yang baik, mengajar tata krama, mengajari menulis, berenang,memanah, menghidupinya dengan rezki yang baik dan menjodohkannya jika sudah memperoleh pasangan”(H.R. Hakim)
Melalui aktivitas basyariahnya yaitu aktivitas tubuhnya maka gagasan dan pemikiran manusia dapat diwujudkan dalam bentuk kongkrit, yaitu dalam bentuk hasil karya dan cipta manusia yang menempati ruang tertentu, dapat diraba, difoto, seperti lukisan, tari-tarian dan kegiatan mengolah besi pada industri logam,14 mengolah pertanian dan perikanan dan lain-lain. Pendidikan dalam hal ini harus mengajarkan keterampilan yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.
Mengutip pernyataan A. Malik Fajar dalam menjelaskan hadis Rasulullah saw “ Kebersihan itu sebagian dari iman” tidak hanya diartikan menjaga kebersihan badan, perumahan, pakaian, dan lingkungan, tetapi dapat juga dipertajam misalnya dengan pengertian menciptakan alat-alat pembersih seperti
13 Muhammad Tolha Hasan, Dinamika kehidupan Religius, (Jakarta: Lista Fariska Putra,
2004), hal.133 14 Abudin Nata, Pendidikan dalam Perspektif Al-Quran, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005),
hal.7
mesin cuci dan pasta gigi, dan teknologi mesin yang dapat menciptakan suasana menjadi bersih.15
Demikian kecakapan-kecakapan yang harus diwujudkan terhadap peserta didik dalam proses belajar yang tentunya disesuaikan dengan kondisi fisik dan psikis peserta didik. Kecakapan-kecakapan yang ada pada setiap peserta didik sebagai bukti keadilan dan kesempurnaan pencipta-Nya. E. PENILAIAN HASIL BELAJAR PADA ASPEK KOMPETENSI
Ada tiga aspek kompetensi yang harus dinilai untuk mengetahui seberapa
besar pencapaian kompetensi tersebut antara lain16 ;
1. Ranah kognitif (penguasaan materi akademik) Penilaian terhadap ranah kognitif ini bertujuan untuk mengukur
penguasaan konsep dasar keilmuan (content objectivies) berupa materi-materi esensial sebagai konsep kunci dan prinsip utama. Ranah kognitif ini merupakan ranah yang lebih banyak melibatkan kegiatan mental/otak.
Kemampuan-kemampuan dan domain kognitif oleh Bloon dikategorikan lebih terinci secara herarkis dalam 6 jenjang kemampuan proses berpikir mulai dari tingkat terendah sampai tinggi antara lain; 17
1). Hafalan/ingatan (recall), meliputi kemampuan menyatakan kembali fakta, konsep, prinsip dan prosedur yang telah dipelajari
2) Pemahaman (comprehension), meliputi kemampuan menangkap arti dari informasi yang diterima serta mengungkap suatu konsep atau prinsip dengan kata-kata sendiri
3). Penerapan (application), ialah kemampuan menggunakan prinsip, aturan, metode yang dipelajari pada situasi baru atau situasi konkret.
4). Analisis (analyze) meliputi kemampuan menggunakan suatu informasi yang dihadapi menjadi komponen-komponen sehingga struktur informasi menjadi jelas.
5). Sintesis (sintesis) kemampuan untuk mengintegrasikan bagian- bagian yang terpisah menjadi suatu keseluruhan yang terpadu. Termasuk di dalamnya meliputi kemampuan merencanakan eksperimen, menyusun karangan, menyusun cara baru untuk mengklasifikasikan objek, peristiwa dan lain-lain.
15 Malik Fajar, Treorientasi Pendidikan Islam, (Jakarta : 1999), hal.41 16Armai Arif, Pengantar Ilmu dan Metode Pendidikan Islam, (Jakarta : Ciputat Perss, 2002),
hal. 57 17 Harjanto, Perencenaan Pengajaran, (Jakarta: Rineka Citra, 2003), hal. 59
6). Evaluasi (evaluasion) kemampuan untuk mempertimbangkan nilai-nilai suatu pernyataan, uraian dan pekerjaan berdasarkan kriteria tertetu yang ditetapkam
2. Ranah afektif atau sikap/normatif
Hasil belajar proses ini berkaitan dengan sikap dan nilai yang berorientasi keapda penguasaan dan kepemilikikan dan kecakapan proses atau metode. Ciri-ciri hasil belajar ini tanpak pada peserta didik dalam berbegai tingkah laku seperti perhatian terhadap pelajaran, kedisipl,inan, motivasi belajar, rasa hormat dll. Ranah afektif ini dapat dirinci menjadi lima jenjang yang disusun mulai dari yang paling sederhana sampai tahap yang paling kompleks.18
a. Penerimaan atau (receiving) kesediaan seseorang untuk mengikuti suatu peristiwa tertentu
b. Tanggapan (responding) menunjuk pada keikutsertaan secara aktif dari peserta didik agar dapat memberikan reaksi kesiapan dalam memberikan respon atau minat.
c. Penghargaan (Valuing) yaitu berhubungan dengan nilai yang melekat pada peserta didik terhadap suatu peristiwa atau tingkah laku.
d. Pengorganisasian (organization) yaitu menggabungkan beberapa nilai yang berbeda-beda serta membangun sistem yang konsisten secara internal.
e. Karakterisasi terhadap nilai (characterzation by a value) yaitu menjuk proses afeksi dimana seseorang memiliki suatu sistem nilai sendiri yang mengendalikan perilakunya untuk waktu yang lama dan pada gilirannya akan membentuk gaya hidupnya.
3. Ranah psikomotorik (afektif, produktif/ keterampilan)
Hasil belajar ini merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan (skill) atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Ranah ini di bagi atas 7 level belajar yang disusun mulai dari yang paling sederhana sampai tahap yang paling kompleks19;
a. Persepsi (perception) yaitu berkenaan dengan penggunaan organ indra untuk menangkap isyarat yang membimbing aktivitas gerak.
b. Kesiapan (set) yaitu menunjukan pada kesiapan untuk melakukan tindakan atau kesiapan mental dan pisik untuk bertindak.
a. Gerakan terbimbing (guinded respon), yaitu tahap awal dalam mempelajari keterampilan yang kompleks seperti peniruan.
18 Hasyim Zaini, Desain Pembelajaran Perguruan Tinggi, (Yogyakarta: CTDS Sunan kalijaga,
2002), hal.74-76 19 Ibid, hal. 62
b. Gerakan terbiasa (mekanisme) yaitu berkenaan dengan kinerja dimana respon peserta didik telah menjadi terbiasa dan gerakan-gerakan dengan penuh keyakinan dan kecakapan.
c. Gerakan Kompleks (komplex overt respons), yaitu merupakan gerakan yang sangat terampil dengan pola- pola gerakan yang sangat kompleks
d. Penyesuaian pola gerak (adapation) , yaitu berkenaan dengan keterampilan yang dikembangkan dengan baik sehingga peserta didik dapat memodivikasi pola-pola gerkan untuk menyesuaikan tuntutan tertentu.
e. Kerativitas (organization), yaitu menunjuk kepada penciptaan pola-pola gerakan baru untuk menyesuaikan situasi tertentu atau problem khusus.
Hasil belajar psikomotorik merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif dan afektif. Hal ini akan dapat setelah peserta didik menunjukan perilaku atau perbuatan teretentu sesuai dengan makna yang terkandung pada kedua ranah tersebut dalam kehisupan sehari-hari. F. KESIMPULAN
Ternyata aspek pengembangan peserta didik kapanpun dan di manapun butuh perubahan dan itu melalui belajar (baca tulis) akan membawa perubahan (behavior change dan knowledge) yang pada intinya mewujudkan kecakapan baru. Perubahan terjadi karena usaha yang disengaja. Pendidik dituntut memperhatikan faktor-faktor yang bersumber dalam diri peserta didik sendiri, baik fisiologis maupun psikologis. Pendidik harus tanggap dengan kondisi psikis peserta didik dan berupaya mengatasinya.
Ternyata Al-Quran (pendidikan) tidak dikotomi dalam mengantar manusia untuk belajar. Al-quran dengan seruannya disesuaikan dengan kondisi sosial intelektual dan kultural masing-masing audiensi. Kecakapan yang ditawarkan kepada audiensnya terdiri dari tiga kecakapan yakni kecakapan akademik, kecakapan sosial dan kecakapan berkarya.
Ternyata peserta didik dalam memberi nilai atau hasil belajar apakah ranah kognitif, ranah afektif dan ranah pisikomotorik memang sangat relatif. Lantaran itu pendidik biasanya menggunakan alat ukur yang bentuknya teknik tes atau non tes, tergantung pada apa yang hendak diukur, atau informasi apa yang akan dikumpulkan.
BIBLIOGRAFI
Arif, Armai, Pengantar Ilmu dan Metode pendidikan Islam, Jakarta : Ciputat Perss,
2002. Azra, Azyumardi. Esei-Esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam, Jakarta: Logos,
1999. az- Zahroni, Muhammad bin Mathar. Tadwin As-Sunnah an-Nabawiyah wa
Totowwiruhu min al-Quran al-Awwal ila Nihayah al-Quran at-Tasyi al Hijr, Madinah al –Munawwarah: Daar al-Khudari, 1998.
At-Thabathabai, Muhammad Husin. Memahami Esensi al-Quran, Terjemahan Mahyuddin, Jakarta: Lentera, 2000.
Cronbach, Lee J. Educational Psicology, New Harcourt, Grace, 1954. Crow, Laster D. & Alice Crow, Educational Fsicology Human Development and learning. Dja`ali, Psikologi Pendidikan, Jakarta; Program Pascasarjana Universitas Negeri
Jakarta, 2000. Fajar, Malik. Reorientasi Pendidikan Islam, Jakarta : 1999. Harjanto, Perencenaan Pengajaran, Jakarta: Rineka Citra, 2003. Hasan, Muhammad Tolha. Dinamika kehidupan Religius, Jakarta: Lista Fariska
Putra, 2004. Hilgard, E.R. Teoritis of Learning, New York Appleton Century Crofts, 1948. L. Kingsley , Howard & Ralp Garry, The Nature and Condition of Learning, N.J.
Practice Hall, Inc, Engliwood Clifts, 1957. Nata, Abudin. Pendidikan dalam Perspektif Al-Quran, Jakarta: UIN Jakarta Press,
2005. Rasyad, Aminuddin. Teori Belajar dan Pembelajaran, Jakarta: Uhamka Presss,2003. Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Perss, 1987. Uno, Hamzah B. Orientasi baru dalam Psikologi Pembelajaran, Jakarta: Bumi Aksara,
2006. Zaini, Hasyim. Desain Pembelajaran Perguruan Tinggi, Yogyakarta: CTDS Sunan
kalijaga, 2002.
PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF HADIS (SYARH AL-HADIS AL-MAWDHU’I)
Limyah Alamri
Abstract:
There are large number of hadis related to education, and they are available in al -kutub al-tis’ah. This article explains hadis about education which classified int o five sub themes. They are (1) The eminence of educating children. It is found syarah that educating children has more eminence than charity. (2) Urgency of teaching knowledge through education. It is understood that teaching knowledge to others is very important and compulsory for every moslem. (3) Reward for knowledge seeker in education. It is understood that somebody who seek the knowledge in education is going to have reward to be placed in heaven. (4) Concept of fitrah in the world of education. In this case, fitrah of children has to be developed in the process of Islamic education. (5) Shalat education to children. In this hadis, it can be understood that parents’ obligation is to educate their children to do shalat as early as possible since they are seven years old.
Key Words : Pendidikan, perspektif Hadis
A. PENDAHULUAN
Hadis Nabi saw, adalah sumber ajaran Islam setelah Alquran. Dalam berbagai ayat Alquran sendiri dikatakan bahwa kedudukan Muhammad saw sebagai nabi dan Rasul Allah yang mesti diikuti petunjuk-petunjuk-nya.1 Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa hadis-hadis Nabi saw di samping sumber ajaran Islam, juga merupakan bayan li al-Qur’an (penjelas mengenai isi Alquran).
Hadis-hadis Nabi, telah termaktub dalam berbagai kitab hadis2 dan telah beredar di kalangan masyarakat luas. Dalam kitab-kitab hadis tersebut ditemukan banyak tema yang membicarakan tentang pendidikan. Fakta ini, juga membuktikan bahwa hadis-hadis tentang pendidikan yang terdapat dalam kitab-
Penulis adalah dosen tetap Jurusan Syariah STAIN Samarinda, lulusan pascasarjana UIN
Alauddin Makassar
1Ayat-ayat yang berkenaan dengan hal tersebut di atas adalah antara lain ; (a) QS. al-Nisa (4): 80; (b) QS. Ali Imran (3): 32; (c) QS. al-Hasyr (59): 7;
2Misalnya; Shahih al-Bukhariy, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan al-Turmuziy, Sunan al-Nasa‘i, Sunan al-Darimi, Sunan Ibn Majah, Kitab Muwaththa’ Malik, dan Musnad Ahmad ibn Hanbal. Kesembilan kitab hadis ini, disebut al-Kutub al-Tis’ah. Di samping itu, adapula sejumlah kitab hadis yang juga cukup dikenal di masyarakat, namun kitab-kitab dimaksud tidak banyak beredar. Sebagaian dari kitab-kitab itu dapat disebutkan misalnya; Musnad al-Humaydi, Musnad Abu ‘Awanah, al-Mustadrak li al-Hakim, dan al-Sunan al-Kubra li al-Bayhaqy serta yang lainnya.
2
kitab hadis sangat banyak jumlahnya. Bahkan, hadis-hadis tentang pendidikan tersebut, sangat luas pembahasannya dalam kitab-kitab syarah hadis.
Tema pendidikan perspektif hadis, dapat ditelusuri dalam Mu’jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadits al-Nabawiyah melalui lafal tarbiyah, ta’lim, ta’dib, dan lafal-lafal lain yang terkait dengannya misalnya ‘ilmu, al-aql, al-fikr, dan al-hikmah. Khusus lafal ilmu saja, telah ditemukan informasi dari Mu’jam kurang-lebih 822 hadis.3 Lebih dari itu, tema pendidikan dapat pula dianalisis dari lafal fitrah. Kesemua lafal ini, di samping terdapat dalam Mu’jam juga terdapat dalam Miftah Kunus al-Sunnah, dan di era sekarang dapat pula ditelusuri melalui CD Rom Hadis dalam program komputerisasi.
Kaitannya dengan tema pendidikan, maka hadis-hadis yang tidak meng-gunakan lafal tarbiyah, ta’lim, ta’dib, dan lafal-lafal lain yang terkait dengannya tetapi hadis tersebut memiliki kaitan dengan urgensi pendidikan, dapat pula dikategorikan sebagai hadis pendidikan secara tematik. Misalnya saja, hadis tentang perintah untuk mendidik anak menjalankan shalat sejak umur tujuh tahun.
Banyaknya hadis-hadis Nabi saw yang terkait dengan pendidikan, adalah sesuatu yang wajar karena harus diakui bahwa dalam sejarah Nabi saw, diketahui beliau dalam setiap harinya senantiasa mendidik dan mengajar sahabat-sahabatnya. Sistem pendidikan dan pengajaran tersebut disampaikannya secara formal melalui forum majelis ilmu, di samping itu beliau juga menyampaikan pengajaran secara non formal melalui pertemuan-pertemuan yang tidak resmi.
Dapatlah dipahami bahwa Nabi saw selama hidupnya, telah memberi perhatian khusus terhadap masalah pendidikan. Respons dan stimulus Nabi saw terhadap masalah pendidikan ini, paling tidak dapat dilihat dari hadis-hadisnya. Karena itu, dapat dikatakan bahwa ajaran Islamlah yang amat peduli terhadap masalah pendidikan.
Kenyataan di atas, berimplikasi tentang pentingnya penelitian hadis-hadis4 tentang pendidikan yang terdapat dalam berbagai kitab hadis. Lebih penting lagi, bila hadis-hadis tersebut dielaborasi dengan metode tematik (syarh al-mawdhui)5
3A. J. Wensinck, Concordance et Indices De Ela Tradition Musulmanne, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Muhammad Fu’ad ‘Abd. al-Baqy dengan judul al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadits al-Nabawiyah, jilid IV (Leiden: E.J.Brill, 1936), hal. 312-338
4H. M. Syuhudi Ismail menyatakan bahwa latar belakang pentingnya penelitian hadis adalah ; (1) Hadis Nabi sebagai salah satu sumber ajaran Islam; (2) Tidak seluruh hadis tertulis pada zaman Nabi; (3) Telah timbul berbagai pemalsuan hadis; (4) Proses penghimpunan hadis memakan waktu yang lama; (5) Jumlah kitab hadis yang banyak dengan penyusunan yang beragam; (6) Telah terjadi periwayatan secara makna. Uraian lebih lanjut lihat M. Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hal. 75
5Metode tematik (syarh al-mawdhu’i) yang dimaksud di sini adalah membahas hadis-hadis yang berkenaan dengan suatu masalah dalam ajaran Islam, misalnya masalah aqidah, ahkam, akhlak dan lain-lain.
1
3
dengan tetap memperhatikan kegiatan-kegiatan lainnya, seperti kegiatan takhrij al-hadits, naqd al-hadits dan fiqh al-hadits.
B. PENGERTIAN PENDIDIKAN
Kata pendidikan6 pada awalnya berasal dari bahasa Yunani, yakni paedagogie yang terdiri atas dua kata, paes dan ago. Kata paes berarti anak dan kata ago berarti aku membimbing.7 Dengan demikian, pendidikan secara etimologis selalu dihubungkan dengan kegiatan bimbingan terutama kepada anak, karena anaklah yang menjadi obyek didikan.
Selanjutnya, kata pendidikan dalam bahasa Inggris disebut dengan education8 dan dalam bahasa Arab ditemukan penyebutaannya dalam tiga kata, yakni al-tarbiyah, al-ta’līm, dan al-ta’dīb yang secara etimologis kesemuanya bisa berarti bimbingan dan pengarahan. Namun demikian, para pakar pendidikan mempunyai kecenderungan yang berbeda dalam hal penggunaan ketiga kata tersebut.9 Kata al-tarbiyah dalam Lisān al-Arab, berakar dari tiga kata, yakni; raba-yarbu yang berarti bertambah dan bertumbuh; rabiya-yarba yang berarti menjadi besar, dan rabba-yarubbu yang berarti memperbaiki.10 Arti pertama, menunjukkan bahwa hakikat pendidikan adalah proses per-tumbuhan peserta didik. Arti kedua, pendidikan mengandung misi untuk membesarkan jiwa dan memperluas wawasan seseorang, dan arti ketiga, pendidikan adalah memelihara, dan atau menjaga peserta didik.
Mengenai kata al-ta’līm menurut Abd. al-Fattah, adalah lebih universal dibanding dengan al-tarbiyah dengan alasan bahwa al-ta’līm berhubungan dengan pemberian bekal pengetahuan. Pengetahuan ini dalam Islam dinilai sesuatu yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi.11 Berbeda dengan ini, justru al-Attās menyatakan bahwa al-tarbiyah terlalu luas pengertiannya, tidak hanya tertuju pada pendidikan manusia, tetapi juga mencakup pendidikan untuk hewan. Sehingga
6Kata dasar pendidikan, adalah “didik” yang didahului awalan “pe” dan akhiran “an”, yang mengandung arti perbuatan, hal, cara dan sebagainya. Bisa juga berarti memelihara dan memberi latihan (ajara, tuntunan, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 263
7Batasan di atas, dikutip dari Lihat Abu Ahmadi, Ilmu Pendidikan (Cet.I; Jakarta: Rineka cipta, 1991), hal. 69.
8Lihat John Echols dan Hassan Shadili, Kamus Inggris – Indonesia (Jakarta: Gramedia, 1981), hal. 81.
9Sepanjang pengetahuan penulis, kata tarbiyah digunakan oleh Abd. al-Rahmān al-Nahlawi; kata ta’līm digunakan Abd. al-Fattah Jalāl; sedangkan kata ta’dīb digunakan Naquib al-Attās.
10Jamāl al-Dīn Ibn Manzūr, Lisān al-‘Arab, jilid I (Mesir: Dār al-Mishriyyah, t.th), h. 384 dan 389. Luwis Ma’lūf, al-Munjid fī al-Lugah wa A’lām (Cet. XXVII; Bairūt: Dār al-Masyriq, 1997), hal. 243.
11Lihat Abd. al-Fattāh Jalāl, Min U¡ūl al-Tarbawiy fī al-Islām (kairo: Markas al-Duwali li al-Tal’līm, 1988), hal. 17
4
dia lebih memilih penggunaan kata al-ta’dīb karena kata ini menurutnya, terbatas pada manusia.12
Berkaitan dengan uraian-uraian yang telah dikemukakan, dan dengan merujuk pada makna dasar term-term pendidikan tersebut, penulis merumuskan bahwa kata al-ta’dīb lebih mengacu pada aspek pendidikan moralitas (adab), sementara kata al-ta’līm lebih mengacu pada aspek intelektual (pengetahuan), sedangkan kata tarbiyah, lebih mengacu pada pengertian bimbingan, pemeliharaan, arahan, penjagaan, dan pembentukan kepribadian. Karena itu, term yang terakhir ini, kelihatannya menunjuk pada arti yang lebih luas, karena di samping mencakup ilmu pengetahuan dan adab, juga mencakup aspek-aspek lain yakni pewarisan peradaban sebagaimana yang dikatakan Ahmad Fu’ad al-
Ahwaniy bahwa : 13 أن الرتبية عبارة عن نقل احلضارة من جيل إىل جيل (pada dasarnya, term al-
tarbiyah mengandung makna pewarisan peradaban dari generasi ke generasi). Lebih lanjut Muhammad al-Abrāsy menyatakan bahwa al-tarbiyah mengandung makna kemajuan yang terus menerus menjadikan seseorang dapat hidup dengan berilmu pengetahuan berakhlak mulia, mempunyai jasmani yang sehat, dan akal cerdas.14 Dengan demikian, kata tarbiyah lebih cocok digunakan dalam mengkonotasikan pendidikan menurut ajaran Islam.
Masih mengenai pengertian pendidikan, dalam hal ini batasan term tarbiyah, Abdurrahman al-Nahlawi merumuskan bahwa term tersebut sekurang-kurangnya mengandung empat konsep dasar, yakni :
1. Pendidikan merupakan kegiatan yang betul-betul memiliki target, tujuan dan sasaran.
2. Pendidik yang sejati dan mutlak adalah Allah swt. Dialah Pencipta fitrah, Pemberi bakat, Pembuat berbagai sunnah perkembangan, peningkatan dan interaksi fitrah sebagaimana Dia pun mensyariatkan aturan guna mewujudkan kesempurnaan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia.
3. Pendidikan menuntut terwujudnya program berjenjang, peningkatan kegiatan, dan pengajaran selaras dengan urutan juga sistematika menanjak yang membawa anak didik dari suatu perkembangan ke perkembangan lainnya.
12Lihat Muhammad Naquib al-Attās, Aims and Objective of Islamic Education (jeddah: King Abd. al-Azīz, 199), hal. 52
13Ahmad Fu’ad al-Ahwāniy, al-Tarbiyah fīl Islam (Mesir: Dār al-Ma’arif, t.th), hal. 19
14Muhammad Athiyah al-Abrāsy, Rūh al-Tarbiyah wa al-Ta’līm (t.t.: Isā al-Bābī al-Halab, t.th), hal. 14
5
4. Peran seorang pendidik harus sesuai dengan tujuan Allah swt menciptakannya. Artinya, pendidik harus mampu mengikuti syariat agama Allah.15 Berkenaan dengan itulah, maka pendidikan (tarbiyah) yang dimaksud dalam
tulisan ini, adalah proses pembentukan individu berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Melalui proses pendidikan itu, individu dibentuk agar dapat mencapai derajat yang tinggi dan sempurnah (insan kamil), agar mampu melaksanakan fungsinya sebagai ‘Abdullāh dan tugasnya sebagai khalīfatullāh dengan sebaik mungkin. Dari batasan pengertian tentang pendidikan itu, melahirkan berbagai interpretasi yang termuat di dalamnya. Yakni, adanya unsur-unsur edukatif yang sekaligus sebagai konsep bahwa pendidikan itu merupakan suatu usaha, usaha itu dilakukan secara sadar, usaha itu dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab kepada masa depan anak, usaha itu mempunyai dasar dan tujuan tertentu, usaha itu perlu dilaksanakan secara teratur dan sistimatis, usaha itu memerlukan alat-alat yang digunakan.
C. TAKHRIJ DAN KLASIFIKASI HADIS-HADIS TENTANG
PENDIDIKAN Dalam istilah ilmu hadis, takhrij adalah kegiatan pencarian hadis sampai
menemukannya dalam berbagai kitab hadis yang disusun langsung oleh mukharrij-nya. Dalam kitab-kitab tersebut disebutkan hadis secara lengkap dari segi sanad dan matan.16 Dr. H. Arifuddin Ahmad dan pakar hadis lainnya menyatakan bahwa takhrij al-hadis dapat dilakukan dengan metode bi alfaz dan bi al-mawdu’i. Takhrij yang disebutkan pertama berdasarkan lafal dan takhrij yang disebutkan kedua berdasarkan topik masalah.17 Karena kajian ini menggunakan metode tematik, maka takhrij dilakukan adalah takhrij bi al-mawdhu’i. Namun untuk hadis tertentu, tetap digunakan takhrij dengan metode bi alfaz. Pasilitas takhrij yang penulis digunakan adalah kitab Mu’jam dan CD. Rom Hadis melalui program komputer.
Dengan merujuk pada makna yang terkandung dalam term tarbiyah, maka kitab Mu’jam dan CD. Rom Hadis memberikan data-data takhrīj hadis tentang pendidikan sebagai berikut :
1. Takhrīj hadis tentang keutamaan mendidik anak, pada kitab Mu’jam Mufahras ditemukan informasi sebagai berikut :
15Abdurrahman al-Nahlawy, Usul al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Asâlibuha, diterjemahkan oleh Herry Noor Ali dengan judul Prinsip-Prinsip dan Metode Pendidikan Islam (Cet. II; Bandung: IKAPI, 1992), hal. 21
16Lihat M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hal. 43
17Uraian lebih lanjut lihat H.Arifuddin Ahmad, Prof.Dr.H.M.Syuhudi Ismail; Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi (Cet. I; Jakarta: Intimedia dan Insan Cemerlang, 2003), hal. 179-180
6
ألن يؤدب الرجل ولده خري من أن يتصدق بصاع 7الرب ،: ت
17118، 161، 1: حم 2. Takhrīj hadis tentang urgensi mengajarkan ilmu melalui pendidikan, pada
Mu’jam Miftah Kunuz al-Sunnah, ditemukan tema hadis tentang العلم dengan
data-data sebagai berikut :19
_مثل ما بعىن اهلل به من اهلدى والعلم كمل الغيث الكثري * 12ب 3 –بخ
-فضل العلم واألجر عليه * 3و 1ب 14ك –بد 19و 1ب 39ك –تر
Untuk kelengkapan data-data hadis yang bertemakan ilmu, maka penulis juga menggunakan alat bantu CD-Rom. Dengan upaya seperti ini, penulis menemukan informasi yang sejalan dengan data-data hadis yang bersumber dari Miftah Kunuz al-Sunnah, yakni ;
سلسل المصدر حديث الراوى طرف الحديث
1 البخاري 71 عبداهلل احلكمة...الحسد اال ىف اثنني رجل اتاه اهلل ماال
1 البخاري 77 عبداهلل ...مثل ما بعثى اهلل به من اهلدى والعلم 3 مسلم 1331 عبداهلل احلكمة...الحسد اال ىف اثنني رجل اتاه اهلل ماال
4 مسلم 4131 عبداهلل ...اهلل به من اهلدى والعلم إن مثل ما بعثىSumber Data : CD-Rom, al-Kutub al-Tis’ah.
3. Takhrīj hadis tentang balasan yang diperoleh bagi penuntut ilmu dalam pendidikan, juga ditemukan dalam petunjuk Miftah Kunus al-Sunnah dan data CD Rom sebagaimana dalam point nomor 2 di atas. Hal ini disebabkan hadis yang dimaksud di dalamnya terdapat kata al-‘ilmu dan al-hikmah.
4. Takhrīj hadis tentang konsep fitrah dalam dunia pendidikan, pada kitab Mu’jam Mufajras ditemukan informasi sebagai berikut :
...إال يولد على الفطرة ( يولد)مولود ما من 3، قدر 32، تفسري سورة 82جنازة : خ 13قدر : م
18A.J. Wensinck, Concordance., hal. 47 19A. John Wensinck, A Handbook of Earli Muhammadan, diterjemahkan ke dalam bahasa
Arab oleh Muhammad Fu’ad ‘Abd. al-Baqy dengan judul Miftah Kunuz al-Sunnah (Bairut: Dar Ihya al-Turats al-‘Arabiy, 1422 H), hal. 375
7
34920، 313. 1: حم Selanjutnya pada CD. Rom Hadis juga ditemukan informasi bahwa di samping hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Ahmad, juga diriwayat-kan oleh Abu Dawud dalam kitab al-Sunnah, hadis ke-4091.
5. Takhrīj hadis tentang pendidikan shalat bagi anak sejak umur tujuh tahun , ditemukan data yang sama dalam Mu’jam bahwa hadis tersebut dalam Sunan al-Turmuzi kitab al-shalat hadis ke-272, dan Sunan al-Darimi, kitab al-shalat hadis ke-1395.
Dari proses takhrij yang telah dilakukan, maka hadis-hadis tentang pendidikan dapat diklasifikasi lebih lanjut berdasarkan kandungan wurudnya. Klasifikasi hadis yang dimaksudkan diurut berdasarkan tema-tema hadis yang menjadi obyek pembahasan, sebagai berikut : 1. Hadis tentang keutamaan mendidik anak, susunan sanad dan matannya adalah
sebagai berikut :
نا - ث يبة حد نا ق ت ث على بن يي حد صلى الله رس ول قال قال س رة بن جابر عن حرب بن ساك عن ناصح عن ي
يه اهلل ر ولده الرج ل ي ؤدب ألن وسلم عل ق أن من خي تصد وناصح غريب حديث هذا عيسى أمبو قال بصاع ي
21 (رواه الرتمذي) أث بت ه و ... ك وفي العلء أب و ه و نا - ث اهلل صلى ب الن أن س رة بن جابر عن حرب بن ساك عن الله عبد أب ناصح عن الزري ثابت بن علي حد
يه ر ولده أحد ك م أو ولده الرج ل ي ؤدب ألن قال وسلم عل ق أن من له خي وم ك ل ي تصد رواه )صاع بنصف ي 22 ( أمحد
نا - ث اهلل صلى الله رس ول أن س رة بن جابر عن حرب بن ساك عن الله ع ب يد أب ناصح عن ثابت بن علي حد
يه ر ولده الرج ل ي ؤدب ألن قال وسلم عل ق أن من له خي تصد وم ك ل ي الرمحن عبد أمبو قال و صاع بنصف ي
ثن ما ر الله ع ب يد أب ناصح عن أب حد 23 (رواه أمحد) احلديث هذا غي 2. Hadis tentang urgensi mengajarkan ilmu melalui pendidikan, susunan sanad
dan matannya adalah sebagai berikut :
ثن - فيان قال حد ث نا س ث نا احل ميدي قال حد بن أب حد ث ناه الز هري قال سعت ق ي إساعيل بن أب خالد على غري ما حدآتاه الله ماالا فس لط اث نت ني رج ل حازم قال سعت عبدالله بن مسع ود قال قال النب صلى اهلل عليه وسلم ال حسد إال ف
24 (رواه البخاري)على هلكته ف احلق ورج ل آتاه الله احلكمة ف ه و ي قضي با وي علم ها
20Arnold John Wensinck, Concordance., hal. 180 21Abu Isa Muhammad bin Isa al-Turmuzi, Sunan al-Turmuzi, dalam CD. Rom Hadis al-
Kutub al-Tis’ah, hadis ke-1874 22Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, dalam CD. Rom Hadis
Musnad al-Bashriyyin, hadis ke-19995 23Ibid., hadis ke-20065 24Abu ‘Abdullah Muhammad bin Isma’il bin Ibrihim Ibn al-Mugirah bin Bardizbat al-
Bukhari, Shahih, juz I (t.t. Dar Matba’ al-Syabi, t.th), h. 28. Lihat juga dalam CD. Rom Hadis, kitab al-Ilmu, hadis ke-71
8
قال ق - ث نا وكيع عن إسعيل عن ق ي ث نا أب و بكر بن أب شيبة حد ث نا و حد ري حد ث نا ابن ن ال عبد الله بن مسع ود ح و حد قال سعت عبد الله بن مسع ود ي ق وال ث نا إسعيل عن ق ي د بن بشر قاال حد قال رس ول الله صلى اهلل عليه وسلم أب وم م
حكمةا ف ه و ي قضي با وي علم ها حسد إال ف اث نت ني رج ل آتاه الله ماالا فسلطه على هلكته ف احلق ورج ل آتاه الله ال 25 (رواه مسلم)
3. Hadis tentang balasan yang diperoleh bagi penuntut ilmu dalam pendidikan, susunan sanad dan matannya adalah sebagai berikut :
رة قال قال ر - ري نا زائدة عن األعمش عن أب صالح عن أب ه ث حد نا أمحد بن ي ون ث س ول الله صلى اهلل عليه حدل الله له به طريق النة ومن أبطأ به عمل ه ل ي سرع وسلم ما من رج ل يسل ك ط ا إال سه به ريقاا يطل ب فيه علما
26(رواه أو داود)نسب ه
عت عاصم بن - نا عبد الله بن داو د س ث د بن م سرهد حد نا م سد ث يل عن حد وة ي دث عن داو د بن ج رجاء بن حي قال يا أبا ال رداء ف مسجد دمشق فجاءه رج ل ف ا مع أب الد قال ك نت جالسا ي رداء إن جئت ك من كثري بن ق د
ث ه عن رس ول الله صلى اهلل عليه وسلم ما جئت حلامدينة الرس ول صلى اهلل ع لغن أنك ت د جة ليه وسلم حلديث ب ا س عت رس ول الله صلى اهلل عليه وسلم ي ق ول من سلك طريقاا يطل ب فيه علما لك الله به طريقاا من قال فإن س
غفر ل علم وإن العال ليست موات ومن ف ط ر ق النة وإن الملئكة لتضع أجنحت ها رضاا لطالب ال ه من ف السلة البدر على سائر الكواكب وإن األرض واحليتان ف جوف الماء وإن فضل ال قمر لي عال على العابد كفضل ال
ياء ل ي ورث وا ديناراا وال درهاا ورث وا العلم ف بياء وإن األنب د بن من أخذه أخذ بظ واف الع لماء ورثة األن ث نا م م ر حدثن به عن ع ثمان وليد قال لقيت شبيب بن شيبة فحد نا ال ث مشقي حد رداء الوزير الد بن أب سودة عن أب الد
27 (رواه أبو داود) ي عن عن النب صلى اهلل عليه وسلم مبعناه
رة قال - ري نا أب و أ سامة عن األعمش عن أب صالح عن أب ه ث نا مم ود بن غيلن حد ث قال رس ول الله صلى اهلل حدل ا سه فيه علما لتم الله له طريقاا إىل النة قال أمبو عيسى هذا حديث حسن عليه وسلم من سلك طريقاا ي
28 (رواه الرتمذي)
نا عاصم ابن ر - ث ث نا م مد بن يزيد الواسطي حد نا مم ود بن خداش الب غدادي حد ث حد ي وة عن ق بن جاء بن حي و بدمشق ف قال ما أقدمك يا أخي ف ق رداء وه لغن أنك كثري قال قدم رج ل من المدينة على أب الد ال حديث ب
ث ه عن رس ول الله صلى اهلل عليه وسلم قال أما جئت حلاجة ق ال ال قال أما قدمت لتجارة قال ال قال ما ت دبتغي فيه جئت إال ف طلب هذا عت رس ول الله صلى اهلل عليه وسلم ي ق ول من سلك طريقاا ي احلديث قال فإن س
ا سلك الله به طريقاا ها رضاءا لطالب العلم وإن العال ليست غفر علما له من إىل النة وإن الملئكة لتضع أجنحت
25Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairy, Shahih Muslim, juz I (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th), hal. 799. Lihat juga CD Rom Hadis, kitab al-Ilmu, hadis ke-1352
26Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Asy’a£ al-Azdiy, Sunan Abu Dawud, juz III (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.), hal. 317.
27Ibid., hal. 320. 28Abu Isa Muhammad ibn Isa al-Turmuziy, Sunan al-Turmuziy, juz III. Bairut: Dar
al-Fikr, t.th). hal. 276
9
موات ومن ف األرض حت احليتان ف الماء وفضل العال على العابد كفضل الق مر على سائر الكواكب إن ف السا ورث وا الع بياء إن األنبياء ل ي ورث وا ديناراا وال درهاا إن لم فمن أخذ به أخذ بظ وافر قال أمبو الع لماء ورثة األن
نا عيسى وال ن عرف هذا احلد ث ه و عندي مب تصل هكذا حد ي وة ول يث إال من حديث عاصم بن رجاء بن حي وة عن داو ا ي روى هذا احلديث عن عاصم بن رجاء بن حي يل ع مم ود بن خداش هذا احلديث وإن ن كثري د بن ج
رداء عن النب صلى اهلل عليه وسلم وهذا أصح من حديث مم ود بن عن أب الد ي د بن بن ق خداش ورأي م م 29 (رواه الرتمذي)إسعيل هذا أصح
4. Hadis tentang konsep fitrah dalam dunia pendidikan, susunan sanad dan matannya adalah sebagai berikut :
نا ث قعنب حد ري رة أب عن األعرج عن الزناد أب عن مالك عن ال يه اهلل صلى الله رس ول قال قال ه ك ل وسلم عل
واه طرة الف على ي ولد مول ود أب رانه ي هودانه ف ناتج كما وي نص بل ت هل جعاء بيمة من ال يا قال وا جدعاء من ت
رأيت الله رس ول 30 (و داودرواه أب)عاملني كان وا مبا أعلم الله قال صغري وه و ي وت من أف
5. Hadis tentang pendidikan shalat bagi anak sejak umur tujuh tahun, susunan sanad dan matannya adalah sebagai berikut :
نا - ث رنا ح جر بن علي حد رة بن الربيع بن العزيز عبد بن حرملة أخب ه ع عن ال هن سب بن الربيع بن الملك عبد م
رة ه عن أبيه عن سب يه اهلل صلى الله رس ول قال قال جد واضرب وه سنني سبع ابن الصلة الصب علم وا وسلم عل
ها رة حديث عيسى أمبو قال عمر و بن الله د عب عن الباب وف قال عشر ابن علي حديث ال هن معبد بن سب
من العشر ب عد الغ لم ت رك ما وقاال وإسحق أمحد ي ق ول وبه العلم أهل ب عض عند العمل وعليه صحيح حسن
رة عيسى أمبو قال ي عيد فإنه لة الص 31 (رواه الرتمذي)عوسجة ابن ه و وي قال ال هن معبد ابن ه و وسب رنا - نا احل ميدي الز ب ري بن الله عبد أخب ث رة بن ع الربي بن العزيز عبد بن حرملة حد ثن ال هن معبد بن سب عمي حد
رة بن الربيع بن الملك عبد ه عن أبيه عن سب الصلة الصب علم وا وسلم عليه اهلل صلى الله رس ول قال قال جد
ها وه واضرب سنني سبع ابن 32 ( رواه الدارمي)عشر ابن علي Setelah mentakhrij dan mengklasifikasi hadis-hadis tentang pendidikan,
perlu sedikit disinggung tentang naqd al-hadis, yakni kritik tentang kualitas hadis-hadis tersebut. Dalam hal ini, hadis-hadis yang telah dikutip sebelumnya menurut catatan dalam kitab-kitab hadis, dan kitab syarahnya, serta sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan, dinyatakan kesemuanya berkualitas shahih.
29Ibid., hal. 301 30Abu Dawud Sulaiman al-Sijistani, Sunan Abu Dawud, dalam CD Rom Hadis, kitab
al-Sunnah, hadis ke-4091 31Abu Isa Muhammad ibn Isa al-Turmuziy, Sunan al-Turmuziy, dalam CD. Rom,
kitab al-shalat, hadis ke-272 32Sunan al-Darimi, dalam CD. Rom, Kitab al-Shalat, hadis ke-1395.
10
D. SYARAH HADIS TENTANG PENDIDIKAN 1. Keutamaan Mendidik Anak
ر ولده ل الرج ي ؤدب ألن ق أن من خي بصاع ي تصدTerjemah Hadis : Bagi orang tua yang mendidik anaknya dengan baik, sungguh lebih
utama dibandingkan bila ia bersedekah se-sha’
Istilah pendidikan dalam hadis ini, terdapat pada kata “ Jika kata ini .”ي ؤدب
disonimkan dengan makna al-tarbiyah, maka yang digunakan istilah al-ta’dīb yang akar katanya adalah addaba-yu’addibu-ta’dīban yang berarti memberi adab, atau perilaku.33 Kata ini memang tidak ditemukan dalam Al-Qur’an yang mengacu pada makna pendidikan, tetapi dalam hadis kata tersebut banyak disebutkan di
samping dalam matan hadis tadi. Antara lain Nabi saw menyatakan : 34 أدبىن اهلل
(Allah swt telah menanamkan adab/pendidikan pada diriku). Lebih lanjut Naquib al-Attās menyatakan bahwa, istilah pendidikan dengan kata al-ta’dīb sudah mencakup unsur-unsur ilmu (‘ilm), instruksi (ta’līm), dan pembinaan yang baik (tarbiyah).35 Kemudian dalam konseptualnya, kata ta’dīb sudah mencakup unsur-unsur pengetahuan, pengajaran, dan pengasuhan yang baik.36 Dalam perspektif ini, Nurcholish Madjid menyatakan bahwa perkataan al-ta’dīb dalam arti “adab” juga digunakan dalam konteks yang merujuk pada kajian kesusastraaan dan etika profesional dan kemasyarakatan.37 Al-Qur’an menegaskan bahwa contoh ideal bagi orang yang beradab adalah Nabi saw.38 Karena itu, ta’dīb dalam arti pendidikan adalah mengacu pada dimensi akhlak.
Dalam hadis itu, juga disinggung bahwa salah satu dimensi akhlak yang mulia adalah bersedekah, dan merupakan salah satu amal yang terpuji dalam Islam. Bersedekah dapat meringankan beban sesama muslim, sehingga hal tersebut dapat memberikan kegembiraan kepadanya. Dengan bersedekah, maka sangat banyak hal-hal positif yang dapat dilaksanakan. Namun demikian, menanamkan pendidikan ternyata lebih jauh penting dibanding dengan bersedekah. Anak yang terdidik dengan baik akan menjadi anak yang beriman, berakhlak, dan berbudaya. Kapasitas anak yang dilahirkan oleh buah pendidikan
33Luwis Ma’lūf, Al-Munjid fiy al-Lugah (Bairut: Dar al-Masyriq, 1973), hal. 18. 34Abū ‘Abd. Allah Muhammad ibn Ismā’il ibn Ibrahim ibn al -Mugirah ibn al-
Bukhāri, Sahih al-Bukhariy, dalam CD. Rom Hadis, Kitab al-‘Ilm hadis nomor 1211 35Demikian yang dikemukakan al-Attas dalam Wan Mohd. Nor Wan Daud, The
Educational Philosophy and Practice of Syed Muhammad Naquib al -Attas, diterjemahkan oleh Hamid Fahmi, et. all dengan judul Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib al -Attas (Cet. I; Bandung: Mizan, 2003), hal. 174-175, 185, dan 318
36Ibid., hal. 75 37Nurcholish Madjid, Khazanah Intelektual Islam (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintan,
1994), hal. 3 38QS. al-Ahzāb (33): 11
11
ini, terbukti dapat melahirkan anak yang dapat memberikan sedekah yang lebih banyak dibanding sedekah yang diberikan orang tuanya sebanyak sati sha' saja.
Sebaliknya, anak yang tidak terdidik dengan baik dapat saja menghilangkan sedekah yang pernah diberikan kepada seseorang dengan menyakiti hatinya atau bahkan dapat saja merobohkan bangunan yang dibangun dengan sumbangan yang diberikan oleh ayahnya.
Yang menjadi persoalan berikutnya adalah pendidikan yang bagaimana yang diinginkan oleh hadis tadi ?. Diyakini bahwa pendidikan yang diinginkan oleh hadis tersebut adalah adalah pendidikan Islam. Orang Islam menyakini bahwa kehidupan tidak dapat diserahkan seluruhnya kepada kemampuan akal manusia secara pribadi atau manusia dalam arti keseluruhan manusia. Pandangan orang Islam bertolah belakang dari humanisme yang mengajarkan bahwa akal manusia telah mencukupi untuk mengatur dunia dan kehidupan manusia, dan karena itu agama tidak diperlukan.39 Dengan demikian, pendidikan yang diiginkan Nabi saw sebagaimana dalam hadis tersebut, bukanlajh pendidikan yang menanamkan faham humanisme dan pendapat lain yang tidak sejalan dengan ajaran Islam.
2. Urgensi Mengajarkan Ilmu melalui Pendidikan
نت ني رج ل آتاه الله ماالا فس لط على هلكته ف احلق ورج ل آتاه الله و ي قضي با ال حسد إال ف اث احلكمة ف ه ها وي علم
Terjemah Hadis : Tidak boleh mengingkan kepunyaan lain orang melainkan dua macam. Orang yang diberi oleh Allah kekayaan, maka diperguna-kan untuk membela haq (kebenaran) dan orang yang diberi oleh Allah hikmah (ilmu pengetahuan) maka diajarkannya kepada orang lain.
Hadis di atas mengemukakan bahwa al-hikmah bermakna ilmu pengetahuan dalam yang diperoleh dalam proses pendidikan. Term al-hikmah yang bentuk pluralnya adalah al-hikam secara leksikal berarti al-falsafah (kebijaksanaan); al-‘adl (keaadilan); al-hilm (penyantun); dan al-‘ilm (pengetahuan).40 Karena itu, batasan term al-hikmah dengan al-‘ilmu secara harfiyah adalah sama (mutaradifani). Lebih lanjut Ibn Hajar al-Asqalani dalam
men-syarah hadis tersebut beliau menyatakan bahwa لهل وزجر املراد باحلكمة كل مامنع من ا yang dimaksud al-hikmah adalah segala yang terhindar dari kebodohan dan) 41 عن القبيح
segala yang terhalang dari keburukan). Dari sini, dapatlah dipahami bahwa al-hikmah
39Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), hal. 21.
40Louis Ma’luf, Al-Munjid., hal. 146 41Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-Asqlani, Fath al-Bary Sayrh Shahih al-Bukhari, jilid I
(Bayrut: Dar al-Manar, 1990), hal. 205
12
adalah lawan dari al-jahl (kebodohan) dan orang yang berilmu (al-‘alim) juga diterminologikan sebagai lawan dari al-jahil (orang yang bodoh).
Term al-hikmah dalam Alquran42 juga diartikan sebagai al-fahmu wa al-‘ilmu (pemahaman dan pengetahuan) yang berasal dari Allah dan diperoleh setelah berusaha dalam kegiatan dan proses pendidikan.43 Dengan demikian, term al-¥ikmah pada hadis di atas diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia dan ilmu tersebut bersumber dari Allah.
Secara global hadis yang dikaji ini menjelaskan bahwa sikap iri hati (hasad) dibolehkan dalam agama, tetapi hanya dalam dua hal. Pertama, iri hati kepada seseorang yang menggunakan hartanya di jalan kebenaran; dan kedua, iri hati kepada seseorang yang mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Jadi, term hasada pada awal matan hadis tersebut mengandung arti al-gibah (iri yang positif).
Kaitannya dengan itu, Mushtafa Muhammad ‘Imarah menyatakan bahwa
la hasada dalam hadis tersebut bermakna 44 الغبطة اى متىن اخلري والتاف ىف املعاىل artinya,
tidak dilarang untuk iri hati pada cita-cita yang positif dan tidak dilarang pula iri hati untuk berlomba-lomba melakukan amal kebajikan. Lebih lanjut al-Asqalani
juga menyatakan bahwa la hasada dalam hadis tersebut adalah احلسد متىن زوال النعمة عن yakni, al-hasad merupakan keinginan 45 املنعم عليه وخصة بعضهم بأن يتمىن ذلك لنفسه
seseorang untuk mendapatkan nikmat seperti yang dimiliki oleh orang lain, tanpa diiringi dengan keinginan agar kenikmatan itu lenyap dari orang lain dan dari dirinya sendiri. Itu berarti bahwa upaya untuk memperoleh ilmu dengan cara mengaktifkan diri dalam dunia pendidikan adalah sesuatu yang sangat urgen dan signifikan.
Adapun potongan matan hadis di atas yang menyatakan اه الله احلكمة ورج ل آتها ا وي علم و ي قضي ب mengindikasikan bahwa seseorang yang telah diberi hikmah (dari ف ه
Allah) hendaklah orang tersebut mengajarkannya kepada orang lain. Tentu saja, al-hikmah yang dimaksud dalam hadis ini adalah adalah ilmu-ilmu al-din (ilmu agama). Jadi, ilmu agama merupakan karunia Allah yang amat urgen bagi manusia, maka ilmu tersebut urgen pula untuk disampaikan (diajarkan) kepada orang lain. Dengan demikian, makna ilmu pengetahuan yang terinterpretasi dalam hadis yang dikaji ini mencakup kriteria mahmudah (terpuji) dan harus ditransfer kepada orang lain.
42Lihat QS. Luqman (31): 12. 43Abu al-Fida Mujhammad bin Isma’il Ibn Katsir, Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim, jilid III
(Semarang: Toha Putra, t.th), hal. 444. 44Mushtafa Muhammad ‘Imarah, Syarh Riyad al-Shalihin (Bayrut: Dar al-Tsaqafah al-
Islamiyah, t.th), hal. 612 45Uraian lebih lanjut, lihat al-Asqalani, Fath al-Bary., hal. 204.
13
3. Balasan yang Diperoleh Bagi Penuntut Ilmu dalam Pendidikan
ل الله له طريقاا إىل النة ا سه فيه علما تم ل من سلك طريقاا ي Terjemah Hadis : Siapa yang berjalan di suatu jalan menuntut ilmu pengetahuan,
Allah akan memudahkan baginya jalan ke syurga. Hadis lain yang semakna adalah :
ا سلك الله به طريقاا إىل النة وإن الملئكة لتضع أجنح من بتغي فيه علما ها رضاءا لطالب سلك طريقاا ي ت موات ومن ف األرض حت احل غفر له من ف الس عابد العلم وإن العال ليست يتان ف الماء وفضل العال على ال
بياء إن األنبياء ل ي ورث و درهاا ورث وا ا ديناراا وال درهااكفضل القمر على سائر الكواكب إن الع لماء ورثة األن أخذ بظ وافر العلم فمن أخذه
Terjemahnya : Siapa yang melalui suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke syurga; dan para Malaikat selalu melatakkan sayapnya menaungi para pelajar karena senang dengan perbuatan mereka; dan seorang alim dimintakan ampun oleh penduduk langit dan bumi dan ikan-ikan di dalam air. Kelebihan seorang alim atas orang ibadat bagiakan kelebihan sinar bulan atas lain-lain bintang. Sesungguhnya ulama sebagai waris dari nabi-nabi. Sesungguhnya Nabi tidak mewariskan uang dinar atau dirham, hanya mereka mewariskan ilmu agama, maka siapa yang telah mendapatkannya berarti telah mengambil bahagian yang besar. Kedua hadis di atas mengisyaratkan bahwa balasan pahala bagi mereka
yang menuntut ilmu dalam proses pendidikan adalah syurga. Menurut al-‘Abadi, syurga yang dimaksud disini adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Menurutnya, di dunia mereka akan diangkat derajatnya. Dalam QS. al-Mujadalah(58): 11, Allah berfirman :
م وال رفع الله الذين ءامن وا منك علم درجات والله مبا ت عمل ون خبري ي ذين أ وت وا الTerjemahnya :
Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di samping orang yang menuntut ilmu diangkat derajatnya oleh Allah,
maka di akhirat kelak mereka juga akan merasakan kenikmatan yang hakiki dengan menetapnya di syurga. Kebahagiaan syurga tersebut diperuntukkan bagi mereka yang menuntut ilmu (thalib al-‘ilm) dan yang mengamalkan ilmunya
14
(‘amil al-‘ilm) atau yang mengajarkan ilmunya kepada orang lain.46 Karena kedudukan mulia yang diraih oleh Nabi saw, terwariskan kepada ahli ilmu (penuntut ilmu), maka sangat wajar bilamana mereka memperoleh pahala berupa syurga, yakni kemuliaan pada sisi Allah di dunia ini dan di akhirat kelak.
Pada sisi lain, kemuliaan berupa derajat yang tinggi di sisi Allah yang diperoleh para penuntut ilmu tersebut melalui kegiatan pendidikan (menurut hadis), mereka juga senantiasa dilindungi oleh malaikat, termasuk semua penghuni alam ini mendoakannya, karena mereka yang menuntut ilmu tersebut lebih mulia dan lebih baik posisinya bila dibandingkan dengan orang yang beribadah, sebagai-mana indahnya bulan di atas bintang-bintang gemerlap.
Hadis di atas juga mengisyaratkan bahwa sebelum bertingkah laku dan beribadah hendaknya yang diperdalam dalam proses pendidikan adalah ilmu pengetahuan tentang agama terlebih dahulu. Tanpa dasar ilmu agama, maka ibadah yang dijalankan mungkin saja salah atau tidak sesuai dengan amalan Nabi saw. Pada sisi lain, hadis tersebut, juga menegaskan bahwa para ahli ilmu itu adalah pewaris nabi dan diketahui bahwa Nabi saw adalah hamba Allah yang paling mulia kedudukannya.
وي نصرانه ي هودانه فأب واه الفطرة على ي ولد مول ود ك ل Terjemah Hadis : Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka
orangtualah yang akan (mendidiknya) menjadi yahudi dan atau nasrani
Walaupun hadis di atas, tidak menggunakan kata tarbiyah, ta’lim, ta’dib,
ilmu, hikmah, dan yang semakna dengannya, namun hadis tersebut sering kali ditemukan dalam buku-buku pendidikan Islam. Konteks hadis tersebut relevan
dengan QS. al-Rum (30): 30 yang menggunakan kata fitratallahi (فطرت اهلل), yang
mengandung interpretasi bahwa manusia diciptakan oleh Allah mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid.47 Potensi fitrah Allah pada diri manusia ini menyebabkannya selalu mencari yang dipandang sebagai realitas mutlak (ultimate reality), dengan cara mengekspresikannya dalam bentuk sikap, cara berpikir dan bertingkah laku. Dengan sikap inilah sehingga manusia juga disebut sebagai homo educandum (makhluk yang dapat didik) dan homo education (makhluk pendidik), karena pendidikan baginya adalah suatu keharusan guna mewujudkan kualitas dan integritas ke-pribadian yang utuh.
Posisi manusia sebagai homo religious dan homo educandum serta homo education sebagaimana disebutkan di atas, mengindikasikan bahwa sikap keber-
46Uraian lebih lanjut lihat Abu al-Thayyib Muhammad Syams al-Haq al-‘Azim, ‘Aun al-Ma’bb Syarh Sunan Abu Dawud, juz VII (t.t.: al-Maktabah al-Salafiyah, 1979), hal. 51
47Lihat interpretasi yang dikemukakan oleh al-Raghib al-Ashfahani, Mufradat Alfadz al-Qur’an (Cet. I; Beirut: Dar al-Syamiyah, 1992), hal. 640
15
agamaan manusia dapat diarahkan melalui proses pendidikan dengan memandang fitrah sebagai obyek yang harus dikembangkan dan disempurnakan, dengan cara membimbing dan mengasuhnya agar dapat memahami, menghayati dan mengamal-kan ajaran-ajaran keagamaan (Islam) secara universal. Dalam hal ini, Alquran maupun hadis meskipun tidak secara eksplisit membicarakan tentang konsep dasar keberagamaan, tetapi secara implisit dari konteks ayat maupun hadis terdapat petunjuk yang mengarah tentang pendidikan keberagamaan.
Hakekat fitrah keimanan sebagai petunjuk bagi orang tua agar lebih eksis mengarahkan pendidikan anak menuju pada fitrah yang dimiliki oleh anak tersebut secara bijaksana di bawah sejak lahir. Di samping itu, hadis Nabi saw tersebut mengandung implikasi bahwa fitrah merupakan suatu pembawaan setiap manusia sejak lahir, dan mengandung nilai-nilai pendidikan religius dan keberlakuannya mutlak.
Di dalam fitrah mengandung pengertian baik-buruk, benar-salah, indah-jelek dan seterus-nya. Pelestarian fitrah ini, ditempuh lewat pemeliharaan sejak awal (preventif) atau mengembangkan kebaikan setelah ia mengalami penyimpangan (kuratif).48 Fitrah yang dimiliki itu sangat besar dipengaruhi oleh lingkungan, dalam arti bahwa fitrah tidak dapat berkembang tanpa adanya pengaruh positif dari lingkungannya yang mungkin dapat dimodifikasi atau dapat diubah secara drastis bila lingkungan itu tidak memungkinkan untuk menjadi fitrah itu lebih baik. Faktor-faktor yang bergabung dengan fitrah dan sifat dasarnya bergantung pada sejauhmana interaksi dengan fitrah itu berperan.
Pada sisi lain, tentu saja fitrah atau dalam hal ini sikap keberagamaan yang dibawa oleh setiap manusia sejak kecil, pada perkembangannya nanti akan mengalami tingkatan-tingkatan yang bervariasi, sesuai dinamika dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor pertama yang mempengaruhi tingkat keberagamaan adalah pengaruh pendidikan dalam lingkungan keluarga, sebagai unit pertama dan institusi pertama anak dipelihara, dibesarkan dan dididik.
Lingkungan keluarga di sini (orangtua) memberikan peranan yang sangat berarti dalam proses pendidikan keberagamaan anak. Sebab di lingkungan inilah anak menerima sejumlah nilai dan norma yang ditanamkan sejak awal kepadanya. Kaitannya dengan itu, Prof. Dr. H. Mappanganro, MA menyatakan bahwa pada masa-masa tersebut keimanan anak belum merupakan suatu keyakinan sebagai hasil pemikiran yang obyektif, tetapi lebih merupakan bagian dari kehidupan alam perasaan yang berhubungan erat dengan kebutuhan jiwanya akan kasih sayang, rasa aman dan kenikmatan jasmaniah. Peribadatan anak pada masa ini masih merupakan tiruan dan kebiasaan yang kurang dihayati.49 Peniruan sangat
48lihat Mudhor Ahmad, Manusia dan Kebenaran (Surabaya: Usaha Nasional, 1989), hal. 31-32
49Mappanganro, Masa Kanak-Kanak dan Perkembangan Rasa Keagamaan dalam “Warta Alauddin” Tahun XII No. 66 (Ujungpandang: IAIN Alauddin, 1993), hal.16
16
penting dalam kehidupan anak, mulai dari bahasa, mode, adat istiadat dan sebagainya. Hampir semua kehidupan anak berpangkal pada proses peniruan. Misalnya saja, apabila anak-anak itu melihat orang tuannya shalat, maka mereka juga mencoba untuk mengikutinya.
4. Pendidikan shalat bagi anak
ها واضرب وه سنني سبع ابن الصلة الصب علم وا عشر ابن علي
Terjemah Hadis : Ajarkanlah anak (mu) untuk shalat sejak umur tujuh tahun dan pukullah mereka (ketika meninggalkan shalat) dalam umur 10 tahun.
Shalat adalah tiang agama (الصلة عماد الني), dan karena itulah maka perintah
untuk mendidik anak dilakukan sejak dini, yakni sejak anak berusia tujuh tahun ( سبع Pendidikan shalat dalam usia dini, lebih awal dimulai oleh usaha orang .(سنني
mendidik anaknya dalam bentuk hadhana. Hal ini seiring dengan fase perkembangan anak, dan ketika ia mulai memiliki potensi-potensi biologis, paedagogis, mulailah diperlukan adanya pembinaan, pelatihan, bimbingan, pengajaran dan pendidikan yang disebut al-hadhānah.
Hadhanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksana urusannya dan orang yang mendidiknya. Pendidikan yang yang paling penting ialah pendidikan anak kecil dalam pangkuan ibu bapaknya. Karena dengan pengawasan dan perlakuan mereka kepadanya secara baik akan dapat menumbuhkan jasmani dan akalnya, membersihkan jiwanya serta mempersiapkan diri anak menghadapi kehidupannya di masa datang.50
Proses pembinaan spiritual anak lebih efektif lagi bila dalam usia dininya ini, dilatih untuk melaksanakan ibadah. Kemudian pada umur tujuh tahun sebagaimana dalam hadis tadi, hendaknya mereka diperintahkan untuk mendirikan shalat secara kontinyu. Ketika mereka mencapai umur sepuluh tahun dan ketika itu pula mereka meninggalkan shalat, maka hendaklah diberi sanksi fisik berupa pukulan.
Dari hadis di atas, dipahami bahwa di samping adanya perintah mendidik dan membiasakan anak-anak untuk mengerjakan shalat, juga ada perintah untuk memisahkan anak-anak dari tempat tidurnya. Maksudnya, sejak usia dini anak-anak tersebut harus berpisah tempat tidur dengan orang tuanya dan berpisah tempat tidur dengan saudara-saudaranya yang berlainan jenis kelamin. Hal ini dikarenakan pada fase ini, sang anak mulai aktif dan mampu memfungsikan potensi-potensi indranya, ia sudah mulai mengenal mana yang wajar dan yang tidak wajar, mana yang negatif dan yang positif.
50Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah diterjemahkan oleh Moh. Thalib dengan judul Fikih Sunnah, jilid VIII (Cet. VII Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1992). hal. 161-162
17
Pendidikan yang strategis bagi anak sejak dini di lingkungan rumah tangga, merupakan sesuatu yang esensial dalam menjaga fitrah-nya, dan dalam lingkungan itu pula anak telah memperoleh percikan sifat-sifat kesempurnaan Ilahi.51 Lebih lanjut tentang pentingnya pen-didikan anak sejak kecil adalah
berdasar pada pernyataan; 52 ألن التعلم ىف الصغر كالنقش على احلجر (karena pengajaran
diwaktu kecil bagaikan mengukir di atas batu). Ini berarti bahwa jika seseorang yang sejak kecilnya diajarkan dan ditanamkan sifat-sifat ketuhanan, maka sifat-sifat itu berbekas sampai masa dewasa dan sulit terhapus sebagaimana susahnya terhapus tulisan di batu.
E. PENUTUP
Berdasar dari uraian-uraian yang telah dikemukakan, dapat dirumuskan bahwa pendidikan sangat penting umat manusia. Pendidikan yang di maksud di sini adalah tarbiyah, yakni proses pembentukan individu berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Melalui proses pendidikan itu, individu dibentuk agar dapat mencapai derajat yang tinggi dan sempurnah (insan kamil).
Hadis-hadis tentang pendidikan sangat banyak jumlahnya, dan terdapat dalam al-kutub al-tis’ah. Hadis-hadis tentang pendidikan itu, pada dasarnya dapat terklasifikasi atas lima sub tema, yakni (1) keutamaan mendidik anak. Dalam hadis ini, ditemukan syarah bahwa mendidik anak lebih utama dan lebih mulia daripada bersedekah; (2) urgensi mengajarkan ilmu melalui pendidikan. Dalam hadis dipahami bahwa mengajarkan ilmu kepada orang lain sangat penting dan menjadi kewajiban bagi setiap muslim; (3) balasan yang diperoleh bagi penuntut ilmu dalam pendidikan. Dalam hadis ini dipahami bahwa seseorang yang menuntut ilmu dalam dunia pendidikan akan mendapatkan balasan pahala berupa surga; (3) konsep fitrah dalam dunia pendidikan. Dalam hadis ini dipahami bahwa fitrah seorang anak harus dikembangkan melalui proses pendidikan yang Islami; (4) pendidikan shalat bagi anak. Dalam hadis ini dipahami bahwa kewajiban orangtua adalah mendidik anak-anaknya untuk melaksanakan ibadah shalat sejak dini, yakni sejak umur tujuh tahun.
Hadis-hadis yang telah diklasifikasi, dan disyarah secara maudhui, berkualitas shahih. Karena itu, kajian penulis di sini berimplikasi pada pentingnya pengamalan hadis-hadis tentang pendidikan dalam kehidupan.
51Lihat lebih lanjut dalam Achmadi, Ideologi Pendidikan Islam (Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 44
52Lihat Ahmad Fu’ad al-Ahwāniy, al-Tarbiyah fīl Islam (Mesir: Dār al-Ma’arif, t.th), hal. 242
18
BIBLIOGRAFI
Al-Abadi, Abu al-Thayyib Muhammad Syams al-Haq al-‘Azim, ‘Aun al-Ma’bb
Syarh Sunan Abu Dawud, juz VII. t.t.: al-Maktabah al-Salafiyah, 1979. Al-Abrāsy, Muhammad Athiyah. Rūh al-Tarbiyah wa al-Ta’līm. t.t.: Isā al-Bābī al-
Halab, t.th. Achmadi, Ideologi Pendidikan Islam. Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005. Ahmad, H.Arifuddin. Prof.Dr.H.M.Syuhudi Ismail; Paradigma Baru Memahami Hadis
Nabi. Cet. I; Jakarta: Intimedia dan Insan Cemerlang, 2003. Ahmad, Mudhor. Manusia dan Kebenaran. Surabaya: Usaha Nasional, 1989 Al-Ahwāniy, Ahmad Fu’ad. al-Tarbiyah fīl Islam. Mesir: Dār al-Ma’arif, t.th. Al-Ashfahani, al-Raghib. Mufradat Alfadz al-Qur’an. Cet. I; Beirut: Dar al-
Syamiyah, 1992. Al-Asqlani, Ahmad bin ‘Ali bin Hajar. al-Asqlani, Fath al-Bary Sayrh Shahih al-
Bukhari, jilid I Bayrut: Dar al-Manar, 1990. Al-Attās, Muhammad Naquib. Aims and Objective of Islamic Education. jeddah: King
Abd. al-Azīz, 1999. Al-Azdiy, Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Asy’as . Sunan Abu Dawud, juz III.
Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th. Ibn Hanbal, Abu Abdullah Ahmad. Musnad Ahmad bin Hanbal, dalam CD. Rom
Hadis Musnad al-Bashriyyin. Ibn Katsir, Abu al-Fida Mujhammad bin Isma’il. Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim, jilid
III. Semarang: Toha Putra, t.th. Imarah, Mushtafa Muhammad. Syarh Riyad al-Shalihin. Bayrut: Dar al-Tsaqafah
al-Islamiyah, t.th. Ismail, M. Syuhudi. Kaedah Kesahihan Sanad Hadis. Jakarta: Bulan Bintang, 1988 . Metodologi Penelitian Hadis. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1992. Ma’lūf, Luwis. Al-Munjid fiy al-Lugah. Bairut: Dar al-Masyriq, 1973 Madjid, Nurcholish. Khazanah Intelektual Islam. Cet. III; Jakarta: Bulan Bintan,
1994 Mappanganro, Masa Kanak-Kanak dan Perkembangan Rasa Keagamaan dalam
“Warta Alauddin” Tahun XII No. 66. Ujungpandang: IAIN Alauddin, 1993
Al-Nahlawy, Abdurrahman. Usul al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Asâlibuha, diterjemahkan oleh Herry Noor Ali dengan judul Prinsip-Prinsip dan Metode Pendidikan Islam. Cet. II; Bandung: IKAPI, 1992.
Al-Qusyairy, Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim. Shahih Muslim, juz I Bandung: Maktabah Dahlan, t.th
Sabiq, Sayyid. Fiqh al-Sunnah diterjemahkan oleh Moh. Thalib dengan judul Fikih Sunnah, jilid VIII. Cet. VII Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1992.
19
Tafsir, Ahmad. Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994.
Al-Turmuziy, Abu Isa Muhammad ibn Isa. Sunan al-Turmuziy, juz III. Bairut: Dar al-Fikr, t.th
Wan Daud, Wan Mohd. Nor. The Educational Philosophy and Practice of Syed Muhammad Naquib al-Attas, diterjemahkan oleh Hamid Fahmi, et. all dengan judul Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib al-Attas. Cet. I; Bandung: Mizan, 2003
Wensinck, A. J.. Concordance et Indices De Ela Tradition Musulmanne, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Muhammad Fu’ad ‘Abd. al-Baqy dengan judul al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadits al-Nabawiyah, jilid IV. Leiden: E.J.Brill, 1936
. A Handbook of Earli Muhammadan, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Muhammad Fu’ad ‘Abd. al-Baqy dengan judul Miftah Kunuz al-Sunnah. Bairut: Dar Ihya al-Turats al-‘Arabiy , 1411 H.
MAHASISWA ISLAM DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN GLOBAL
Muhammad Nasir Abstract : Development of science and technology has given an impact to every aspect of this life. It has to be quickly responded by Islamic college students as the effort to cope with various problems as a result of the development. History has proven that Islamic college students have played a significant role in the life our state. They have played their role from time to time in four eras; (1) Values breaker, (2) Physical revolution, (4) Politics inside the campus, (5) Role enhancement of college students in the national development. However, Islamic college students still have to deal with various challenges in the global era related to their status as the intellectual moslem. Those challenges are classified into two perspectives. The first one is internal such as less understanding of moslem society about Islamic principles, less qualification of education, fanaticism of Islamic schools, and friction of among the Islamic community. The second one is external from non moslem community. Key words : Mahasiswa Islam, Pendidikan Global A. PENDAHULUAN
Dunia abad 21 akan memasuki babak baru di dalam peradaban umat manusia. Milenium ketiga merupakan abad informasi sesudah masa industri yang juga ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan yang pada prinsipnya dapat dimiliki oleh semua manusia. Karena itu pula pada masa itu disebut dengan era munculnya suatu masyarakat belajar (learning society) atau suatu masyarakat ilmu pengetahuan (knowledge society). Hal Ini berarti bahwa seseorang yang dapat survive adalah orang-orang yang menguasai ilmu pengetahuan.
Di dalam masyarakat ilmu pengetahuan (knowledge society) tentu saja “mahasiswa Islam” sebagai masyarakat yang memiliki integritas dan intelektual diharapkan peka dan cepat merespon segala berntuk perubahan sekaligus memberi jawaban terhadap segala persoalan yang muncul sebagai akibat dari kemajuan Ilmu pengetahuan dan Teknologi. Pada masa ini, masyarakat kampus diharapkan tidak lagi hanya menjadi masyarakat “konsumen” atau masyarakat pendengar, pemakai dan penonton tetapi mampu menjadi masyarakat “produsen”. Yang menjadi pelaku dari skenario perkembangan zaman.
Penulis adalah dosen tetap Jurusan Tarbiyah, doktor lulusan program pascasarjana
UPI Bandung. Kini menjabat sebagai asisten direktur program pascasarjana STAIN Samarinda
Dalam satu sisi, memang ada anggapan bahwa mahasiswa dewasa ini semakin “mandul” karena dianggap tidak mampu memecahkan persoalan umat bahkan justru dianggap mahasiswa merupakan bagian dari masalah itu sendiri. Anggapan ini tentu saja tidak serta merta dibenarkan, tetapi juga seluruhnya tidak boleh disalahkan. Karena secara realitas kadang-kadang mahasiswa memang merupakan bagian dari masalah itu. Harapan kepada mahasiswa untuk melakukan pembaruan ternyata sangat ironis jika terdapat diantara para mahasiswa Islam yang tidak mampu membaca dan menulis Alqur’an, terlebih memahami kandungan Alqur’an. Barangkali telah terjadi pergeseran nilai yang telah menyebabkan perubahan peranan mahasiswa dalam kedudukannya sebagai calon pemimpin masa depan dan kurangnya sikap idealisme yang miliki dan terkesan lebih statis. B. PERAN MAHASISWA DARI MASA KE MASA
Apa bila kita melihat perjalanan kehidupan masyarakat dan bangsa kita, maka tampak adanya perubahan nilai-nilai, baik nilai budaya maupun nilai politik yang menyertai kehidupan bangsa ini. Dalam kehidupan mahasiswa juga tampak adanya pergeseran nilai sejalan dengan perubahan nilai dalam masyarakat. Bukankah mahasiswa adalah sekelompok elit masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk melihat jauh ke depan atau setidak selangkah lebih maju dari masyarakat banyak. Terlebih di dalam suatu masyarakat yang relatif masih rendah tingkat pendidikannya maka peranan mahasiswa sangat menentukan. Di dalam sejarah perkembangan masyarakat Indonesia dapat kita perhatikan empat peranan mahasiswa yaitu era pendobrak nilai, era revolusi fisik, Era politik masuk kampus dan era pemantapan peran mahasiswa dalam pembangunan nasional.1
1. Era Pendobrak Nilai-Nilai
Pada era kebangkitan nasional pertama, mulai dikembangkan pandangan yang melihat betapa kehidupan masyarakat dan bangsa kita menderita akibat kolonialisme. Nilai-nilai yang dilaksanakan di dalam tatanan hidup kekuasaan kolonial telah menjadikan bangsa ini sebagai bangsa hina, dalam bahasa politik bangsa kita adalah bangsa kuli dari bangsa lain. Dengan sendirinya kemajuan dan nilai-nilai kemanusiaan tidak memperoleh tempat yang layak dalam kehidupan. Keadaan ini mendapat perhatian dari para pemuda yang telah mendapat pendidikan dari penjajah. Jika kita telusuri gerakan nasional pada era kebangkitan nasional pertama, maka tidak dapat disangkal dan dipungkiri, sikap kepeloporan dari pelajar dan mahasiswa baik dalam negeri maupun yang telah memperoleh kesempatan belajar di luar negeri
1 H.A.R Tilaar, Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Dalam perpektif Abad 21,
Cet.IV ( Magelang : Indonesia Tera, 2001) hal. 365-367
pada waktu itu. Merekalah sekelompok elit pada saat itu yang melakukan pendobrakan terhadap nilai-nilai lama yaitu nilai lama yang menghambat kemajuan dan nilai kolonial yang menindas kemajuan bangsa Indonesia.
2. Era Revolusi Fisik
Sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tradisi pelajar dan mahasiswa sebagai pendobrak nilai juga telah ikut menghiasi revolusi fisik Indonesia. Di dalam perang kemerdekaan, peranan pelajar dan mahasiswa seperti terlihat di dalam tentara pelajar yang tergabung dalam IPPI. Belajar sambil berperang, merupakan romantika kehidupan mahasiswa pada masa revolusi fisik.
3. Era Politik Masuk kampus
Era ini mahasiswa tidak terlepas dari kancah perjuangan politik. Masa ini terjadi pertarungan kekuasaan politik yang juga memasuki kampus-kampus bukan hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Kita mengenal betapa kampus kampus telah merupakan bagian dari pertarungan perebutan kekuasaan politik yang telah melibatkan kehidupan mahasiswa di dalam kegiatan politik praktis. Di negara kita saat itu, kampus telah dikuasai oleh agitasi politik sehingga kegiatan dan fungsi perguruan tinggi sebenarnya sebagai kampus telah berubah menjadi arena perebutan kekuatan politik.
4. Era Pemantapan Peran Mahasiswa dalam Pembangunan Nasional
Era ini merupakan upaya penataan kembali fungsi kampus sebagai lembaga akademik yang menyiapkan generasi muda agar memiliki kemampuan intelektual yang unggul. Usaha ini bukanlah merupakan hal yang mudah karena kampus kita belum mempunyai tradisi yang kuat, kita masih mencari kehidupan kampus yang sebenarnya. Lantas saat ini, saatnya mahasiswa Islam memperlihatkan taringnya dalam berupaya membekali diri untuk menjadi intelektual Muslim.2 Intelektual muslim yang dimaksud di sini adalah lapisan muslim yang terdidik yang mempunyai peran dalam mengembangkan nilai-nilai budaya. Menurut Muhammad Nasir dalam bukunya Peranan Cendikiawan Muslim, kaum intelektual muslim adalah para cendikiawan yang benar-benar bernafaskan Islam, pemikiran mereka terikat bukan pada ilmu dan teologi tetapi ideologi Islam yang menjadi landasan berpikir dan pandangan hidupnya, keterikatan mereka terhadap ajaran Islam tidak bisa ditawar-tawar karena
2 Intelektual secara harfiah berasal dari bahasa Inggris “Intellectual”. Dalam fungsinya
sebagai kata sifat kata ini berarti Intelektual cerdik cendikia. Lihat, John M. Echol dan Hassan sadly, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta : Gramedia, 1981) hal. 326. Dalam bahasa Arab intelektual adalah ‘Aqil, yang berarti orang yang berakal, orang yang mengetahui, berbudaya, akal pikiran.Lihat, Ilyas, al-Qamus al-Ashry Injilis Arabi, (Kairo : al-maktabah al-Ashriyah, 1968) hal. 365.
mereka adalah intelektual yang menghayati Islam dan memperjuangkan kehidupan Islam di dalam masyarakat.3 C. BEBERAPA TANTANGAN MAHASISWA ISLAM
Sesungguhnya mahasiswa Islam memiliki multi tantangan di era global ini jika dikaitkan dengan predikat intelektual muslim yang dilekatkan padanya. Tantangan itu dapat berupa tantangan internal kaum muslimin seperti kurangnya pemahaman masyarakat muslim terhadap ajaran agama Islam, rendahnya tingkat pendidikan, adanya fanatisme aliran dan mazhab, adanya perpecahan di kalangan umat Islam dan lain-lain, atau tantangan eksternal dari kaum non muslim. Tanpa menafikan tantangan lain, berikut ini kita lihat dua tantangan yang dianggap memerlukan solusi yang cepat dan tepat.
1. Meluruskan image Barat tentang masyarakat muslim
Fanatik, tidak berkompoten, fundamentalis, biadab, teroris, otokratis,
haus darah, inilah beberapa atribut yang diberikan oleh Barat untuk menggambarkan kaum muslimin dan masyarakat muslim. Dalam ilmu pengetahuan dan literatur maupun dalam jurnalisme dan fiksi populer kaum muslimin digambarkan sebagai kaum ganas yang haus darah memotong tangan pencuri, merajam wanita pezinah hingga mati atau mencambuk orang yang meminum alkohol.
Untuk mencemarkan Islam, Barat menciptakan sejumlah teknik di antaranya, pemroyeksian terang-terangan image Islam dengan menggunakan label-label. Islam dipandang sebagai sisi gelap Eropa, maka ketika Eropa beradab, Islam dianggap biadab. Ketika Eropa mencintai perdamaian, maka kaum muslimin garang dan haus darah. Di Barat ada tradisi demokratis dan cinta damai, maka kaum muslimin despotis dan kejam. Sementara Eropa bermoral dan bijak, maka kaum muslimin amoral dan bejat.
Image tentang Islam dan masyarakat-masyarakat muslim ini masih hidup dan diabadikan oleh buku-buku fiksi baru seperti Haj karya Leon Uris, Horn Of Afrika karya Philip Caputo dan lain-lain.4 Oleh karena itu, tugas dan tantangan kita sebagai kaum intelektual muslim tentu berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mencari cara guna meluruskan image yang 100% tidak benar itu.
3 Muhammad Nasir, Peranan Cendekiawan Muslim, (Jakarta : DDII, 1978) hal. 2
bandingkan dengan Delian Noor, Masalah Ulama Intelektual atau intelektual Ulama, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974 M), hal. 8 Lihat pula Ziauddin Sardar, The Future of Muslim Civilization, (London : Croom Helm, 1979 M) hal. 67.
4 Zainuddin Sardar, Information and The Muslim World a Strategy For The Twenty Fist Century, terj. oleh A.E Priyono dan Ilyas Hasan, dengan judul Tantangan Dunia Islam Abad 21 menjangkau informasi, Cet. VII ( Bandung : Mizan, 1996) hal. 115-116
2. Mempromosikan komunikasi ilmu dan teknologi Negara-negara muslim mutlak perlu mengembangkan dan
mempromosikan sumber-sumber tradisional komunikasi seperti jurnal-jurnal ilmiah dan pendirian jaringan-jaringan informasi yang dirancang secara khusus untuk menyatukan dan memajukan serta pertukaran gagasan antara para ilmuwan dan intelektual muslim. Dunia muslim sangat kekurangan jurnal ilmiah karena itu tugas dan tanggungjawab mahasiswa Islam ke depan adalah menerbitkan sejumlah jurnal primer dan sekunder yang khusus untuk para ilmuwan dan intelektual muslim untuk melayani dunia Islam.5
Untuk merealisasikan cita-cita ini, tentu saja mahasiswa hendaknya menciptakan tradisi ilmiah dengan terbiasa menulis dan melakukan penelitian ilmiah berdasarkan disiplin ilmu yang dimiliki. Sehingga pada akhirnya mereka ahli dibidangnya. Menulis dan mrelakukan penelitian tentu saja membutuhkan keahlian. Sehingga tulisan atau jurnal atau apapun namanya dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan dunia Islam. Diharapkan tulisan atau jurnal dan penelitian yang ada nanti tidak hanya mendiskripsikan teori, tetapi lebih pada pengujian teori atau penemuan teori. D. POTRET MAHASISWA ISLAM SEBUAH HARAPAN
Dalam rangka menjawab tantangan-tantangan di atas, tentu saja
beberapa hal yang wajib dimiliki oleh umat Islam khususnya mahasiswa adalah sebagai berikut :.
1. Mahasiswa Islam pada masa yang akan datang hendaknya memiliki
Sumber Daya Unggul (SDM).
Masyarakat saat ini, terlebih masa yang akan datang, adalah masyarakat terbuka, artinya komunikasi antara manusia di dalam berbagai arena kehidupan akan bebas dari hambatan-hambatan. Di dalam bidang politik, arus demokratisasi sedang melanda dunia, hancurnya tembok berlin yang melambangkan kehidupan kediktatoran, hancurnya komunisme dengan leburnya Uni soviet serta tersingkapnya tirai bambu dari Cina Komunis yang dewasa ini telah menganut paham kebebasan berusaha, seluruhnya menunjukan bahwa proses demokratisasi tidak terbendung lagi. Sejalan dengan proses tersebut, semakin menguat pula pengakuan terhadap hak asasi manusia yang muncul di seluruh permukaan bumi. Hal ini berarti era globalisasi telah menempatkan manusia sebagai titik sentral dalam kehidupan. Maka apabila manusia dijadikan sebagai titik sentral, maka pembangunan yang dilaksanakan tidak lain merupakan pembangunan yang berorintasi pada pengembangan Sumber Daya Manusia.
5 Ibid, hal. 158
Adanya dunia tanpa batas, perdagangan bebas, dunia yang terbuka, maka umat manusia lebih saling mengenal. Lebih saling mengenal kemampuan satu bangsa, saling mengetahui kekayaan dan kebudayaan bangsa lain, maka dengan sendirinya manusia semakin memperoleh pengetahuan dan pilihan yang lebih banyak. Manusia yang dapat memilih adalah manusia yang dapat berpikir, manusia yang mengetahui hak-hak dan kewajibannya. Manusia yang tidak memiliki kemampuan berpikir dan berkarya, adalah manusia yang terbatas pilihannya. Oleh karena itu, kehidupan masa datang menuntut manusia Islam unggulan yang menghasilkan karya yang unggul pula. Karena dengan sendirinya hanya manusia unggul yang dapat servive di dalam kehidupan yang penuh persaingan dan menuntut kualitas kehidupan.
Kaitannya dengan hal ini, maka kita dapat membedakan dua jenis manusia unggul yaitu Pertama, keunggulan Individualistik dan Kedua, keunggulan Partisipatorik.6 Yang dimaksud dengan Keunggulan Individualistik adalah manusia yang unggul tetapi keunggulan tersebut hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Keunggulan yang diperolehnya diabdikan untuk mengumpulkan harta benda untuk kepuasan sendiri (hedonisme) atau memupuk kekuasaan. Manusia-manusia yang unggul secara individualistik adalah manusia rakus, yang saling mematikan satu dengan yang lain. Inilah tipe manusia homo Homini Lupus. Jelas bahwa manusia unggul individualistik tidak sejalan dengan ajaran agama Islam. Sementara manusia unggul yang kedua adalah manusia yang memiliki Keunggulan Partisipatoris yaitu manusia unggul adalah manusia yang ikut secara aktif di dalam persaingan yang sehat untuk mencari hasil yang terbaik. Persaingan sehat berarti tidak mematikan sesama manusia, bahkan saling membantu untuk kepentingan bersama. Bukankah Nabi Muhammad saw. menyatakan “ Sebaik-Baik Manusia adalah yang paling banyak manfaatnya dengan sesamanya”
Untuk mewujudkan “ manusia unggul partisipatoris” menurut H.A.R Tilaar dengan mengutip Istilah yang digunakan Dr. Marta Thilaar ada beberapa sikap yang perlu dimiliki yaitu : a. Dedikasi dan disiplin. Seorang manusia unggul haruslah mempunyai rasa
pengabdian terhadap tugas dan pekerjaannya, dia harus sadar arah. atau dia harus memiliki visi yang jelas dan jauh ke depan. Visi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam visi strategis yaitu visi yang dijabarkan ke dalam target-target dan terikat dalam kurung waktu tertentu yang perlu diwujudkan. Kemudian seorang yang berdedikasi tinggi adalah seseorang yang berdisiplin karena ia fokus pada apa yang menjadi cita-citanya.
b. Jujur. Kejujuran adalah sangat penting bukan hanya jujur terhadap orang lain, tetapi juga jujur pada diri sendiri. Kejujuran juga terkait pada jujur terhadap kemampuan sendiri. Kita harus jujur terhadap apa yang dapat kita perbuat dan yang tidak dapat kita perbuat. Inilah sikap profesionalisme. Mahasiswa Islam diharapkan menjadi mahasiswa Islam profesional yaitu
6 lihat, H.A. R. Tilaar, Beberapa Agenda Reformasi, hal. 56
mahasiswa yang ahli dalam bidangnya. Kejujuran profesional akan menghasilkan produk yang unggul dan terus menerus dapat bersaing.
c. Inovatif. Manusia unggul adalah manusia yang anti kemapanan, anti kepuasan dengan apa yang telah dicapainya dan anti status quo. Dia selalu gelisah dan mencari sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi diri dan orang lain. Mencari yang baru tidak harus menemukan yang baru, tetapi menemukan fungsi baru dari suatu penemuan. Contoh penemuan Faksimil di Amerika Serikat yang kemudian dikembangkan di Jepang.
d. Tekun. Seorang manusia unggul adalah orang yang dapat memfokuskan perhatian pada tugas dan pekerjaan yang telah diserahkan kepadanya atau suatu usaha yang sedang dikerjakannya. Ketekunan akan menghasilkan sesuatu, karena manusia unggul tidak akan berhenti sebelum menemukan sesuatu.
e. Ulet, manusia unggul adalah manusia yang tidak mudah putus asa. Dia akan terus menerus mencari dan mencari. Dibantu dengan sikapnya yang tekun, maka keuletan akan membawa dia pada dedikasi terhadap pekerjaannya mencari yang lebih baik dan bermutu.7
2. Mahasiswa Islam Harus Belajar Terus Menerus
Dunia yang semakin terbuka dibantu dengan kemajuan ilmu
pengetahuan yang semakin pesat, akan membawa manusia pada suatu dilema akan keterbatasan kemampuan otaknya. Namun demikian, kemajuan teknologi telah dan akan membawa kemampuan otak manusia yang terbatas itu dengan menguasai teknologi komunikasi dan informasi sehingga manusia yang serba terbatas itu dapat hidup di abad informasi dengan information superhighway-nya. Seperti kita ketahui perkembangan ilmu pengetahuan begitu cepat sehingga apa yang dicapai umat manusia selama beberapa abad, telah jauh dilampaui oleh ilmu pengetahuan pada lima puluh tahun terakhir ini. Perkembangan secara eksposional ilmu pengetahuan telah mengubah prinsip-prinsip belajar manusia yang harus dilaksanakannya seumur hidup. Apabila tidak demikian, maka manusia itu akan jauh tertinggal dari arus ilmu pengetahuan dan informasi yang semakin lama semakin besar sehingga pada suatu ketika manusia akan tertimbun olehnya. Adalah sangat menarik perhatian apa yang telah ditelorkan oleh suatu komisi UNESCO dalam mempersiapkan pendidikan manusia masa depan. Menurut UNISCO belajar pada era informasi ini harus didasarkan pada empat pilar yaitu lerning to think, learning to do, learning to be dan learning to live together. Keempat pilar tersebut oleh UNISCO sebagai soko guru bagi manusia mengahadapi era globalisasi.
Proses belajar terus menerus adalah belajar bagaimana berpikir. Dengan sendirinya orang yang terbiasa vakum dan apatis tidak akan
7 Lihat, Ibid, .hal. 57 -59
mempunyai tempat di era globalisasi.8 Sehubungan dengan itu penguasaan bahasa digital telah harus dikuasai oleh generasi Islam karena hanya dengan demikian mereka dapat memasuki dunia tanpa batas. Dengan demikian, konsep belajar dan pembelajaran harus dirubah dan membuka pintu teknologi pembelajaran modern, sungguhpun tetap dibutuhkan pendidikan tatap muka oleh orang tua, oleh dosen dan oleh lembaga kemasyarakatan lainnya dalam rangka pembentukan akhlakul Karimah. Selanjutnya generasi yang diharapkan bukan hanya generasi yang bisa berpikir tetapi generasi yang bisa berbuat. Manusia yang berbuat adalah manusia yang ingin memperbaiki kualitas kehidupannya. Dengan berbuat dia dapat menciptakan produk-produk baru dan meningkatkan mutu produknya. Tanpa berbuat suatu pemikiran atau konsep tidak mempunyai arti. Kehidupan masyarakat abad global adalah kehidupan yang mementingkan mutu. Dalam masyarakat global tidak ada tempat bagi manusia yang tidak berkarya.
3. Meneladani Semangat Tokoh-Tokoh Muslim
Jika kita mencoba menelaah ulang sejarah Islam dengan teliti dari masa
klasik hingga periode modern, maka kita akan mendapat tokoh-tokoh Islam yang ahli dalam bidangnya.9 Dalam bidang Filsafat muncul tokoh al-Kindi, al-Farabi, Ibnu Sina, Ibun Miskawaih, Ibnu Khaldun, Ibnu Thufail, al-Razi dan lain-lain, dalam bidang Tasawuf muncul al-Gazali, Rabiatul Adawiyah, al-Hallaj, Al-Jili, Ibnu Arabi dan lain-lain, di bidang pembaharuan dan pemurnian muncul Muhammad ibn Abdul Wahab, Ibnu Taimiyah, Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha dan lain-lain. Demikian pula pada bidang yang lain muncul tokoh tokoh yang memiliki keistimewaan.
Salah satu di antara tokoh yang dapat diteladani upayanya dalam menjadi intelektual muslim adalah Fazlurrahman10. Berbagai upaya yang ia lakukan untuk menjadi seorang muslim yang memperjuangkan Islam. Di antaranya Ia berangkat ke Inggris pada tahun 1946 untuk melanjutkan studi di Universitas Oxford. Di Universitas terkenal ini, selain mengambil dan mengikuti kuliah-kuliah formal, ia juga giat mempelajari bahasa-bahasa Barat.11
8 Ibid hal. 61 - 63 9Periodesasi Sejarah Islam menurut Harun Nasution terbagi ke dalam tiga periode
yaitu Pertama, Periode Klasik (650 M.-1250M.),Kedua, Periode Pertengahan (1250 M.–1800 M.) dan Ketiga, Periode Modern (1800 M.- sekarang) Lihat Harun Nasution, Islam diTinjau dari Berbagai Aspeknya, Cet. 5 (Jakarta : Universitas Indonesia (UI Press) 1985 M.) hal. 56 – 88
10Ia dilahirkan pada tahun 1919 M. Dan dibesarkan di sebuah keluarga denngan tradisi mazhab hanafi, sebuah mazhab Sunni yang lebih bewrcorak Sunni yang lebih bercorak rasionalitas dibandingkan tiga mazhab sunni lainnya.
11 Fazlurrahman setidaknya telah menguasai sejumlah bahasa di dunia seperti bahasa latin, bahasa Inggris, bahasa jerman, bahasa Turki, bahasa Arab, serta bahasa Urdu. Taufik Adnan Amal, Islam dan Tantangan Modernitas, Studi atas oikiran hukum Fazlurrahman, ( Bandung : Mizan, 1996 ) hal. 81
Penguasaannya terhadap bahasa tersebut pada gilirannya sangat membantu upayanya dalam memperdalam dan memperluas wawasan keilmuannya, khususnya dalam studi-studi keislaman, lewat penelusuran terhadap literatur-literatur keislaman yang ditulis para orientalis dalam bahasa-bahasa mereka. Meskipun banyak menimba ilmu pengetahuan dari Barat, namun demikian, ia sangat kritis terhadap pandangan-pandangan Barat yang bertalian dengan Islam dan umatnya.
Sejogyanya mahasiswa Islam dapat meniru dan meneladani semangat belajar para tokoh yang tercatat namanya dalam sejarah Islam. Baik dalam bidang ilmu-ilmu agama maupun dalam bidang ilmu umum.
Dalam rangka mencapai harapan di atas tentu saja tanggungjawab dan peran perguruan Tinggi sangatlah signifikan. Oleh karena itu, perguruan Tinggi diharapkan tidak hanya mengajarkan hal-hal yang baru akan tetapi harus mengajarkan pula hal-hal berikut ini : 1. Prinsip-prinsip perubahan masyarakat. Diharapkan dengan ini mahasiswa
dapat mempergunakannya sebagai kunci untuk memahami perubahan-perubahan yang akan terjadi kemudian, Mengajarkan kepada mahasiswa pokok-pokok pemikiran sebagai kunci memahami keadaan masyarakat yang selalu mengalami perubahan. Mahasiswa dipersiapkan untuk menjawab persoalan-persoalan yang mungkin timbul 30 atau 40 tahun yang akan datang, karena mereka akan menghadapi masalah yang berbeda dengan masalah yang kita hadapi sekarang. Sejauh menyangkut ajaran Islam, hal-hal yang bersifat vertikal tidak terdapat perubahan akibat perubahan masyarakat. Tetapi hal yang bersifat horisontal (hubungan antar manusia) yang banyak mengalami perubahan, maka kunci untuk memahaminya adalah dengan ijetihad yang dapat ditempuh dengan jalan konsensus atau ijma’ dan dengan jalan qiyas (analogi) dengan segala variasinya sepanjang tidang bertentang dengan prinsip Alqur’an dan Hadis.
2. Menumbuhkan berpikir secara kritis di kalangan mahasiswa. Karena mendidik pada hakekatnya mengantarkan mahasiswa untuk menggali potensi dalam dirinya yang potensial menjadi realitas yang real. Mendidik adalah upaya untuk menghantarkan seseorang agar dapat mengembangkan bakat dan minat yang dimilikinya.
3. Menimbulkan optimisme di dalam mahasiswa dengan menyadarkan bahwa ia adalah orang yang cakap dan mempunyai hari depan yang baik. Dengan demikian akan timbul kegairahan dalam diri mereka untuk memecahkan persoalan pelik yang dihadapi. Seorang mahasiswa adalah orang yang berada pada masa pertumbuhan dan perkembangan pribadinya.
4. Mengajarkan method of approach, cara-cara untuk memecahkan suatu masalah. method of approach adalah suatu hal yang bertahan lama dan tidak cepat mengalami perubahan. Oleh karena itu, dengan pengetahuan method of approach itu, mahasiswa dapat menghampiri masalah masyarakat yang tiap kali mengalami perubahan.
5. Menanamkan disiplin intelektual, berpikir secara konsisten dan memiliki integritas pribasdi, hingga dengan demikian, ia sanggup menghadapi masalah-masalah yang lebih banyak apabila mereka meninggalkan bangku kuliah
6. Mengajarkan dan mengantarkan mahasiswa mencintai buku karena buku adalah sahabat yang tak pernah dusta.12 Dengan penguasaan sistem ilmu yang diajarkan berikut cara pendekatannya ditambah dengan kemampuan bahasa Arab dan Inggris, maka dunia ilmu pengetahuan mahasiswa akan terbuka lebar, ufuk pandangan dan perspekytif pemikirannya lebih luas.
E. PENUTUP
Pada akhirnya mahasiswa Islam harus mempersiapkan diri sedini mungkin dengan membekali diri dengan kompetensi sesuai bidang keahliannya agar predikat mahasiswa Islam unggulan pantas melekat padanya, yaitu unggul dalam kecerdasan Intelektual, unggul dalam kecerdasan Emosional dan unggul dalam kecerdasan Spritual.
BIBLIOGRAFI
Amal, Taufik Adnan., Islam dan Tantangan Modernitas,Studi atas Pikiran hukum
Fazlurrahman, Bandung : Mizan, 1996 Azra, Azyumardi., Esei-esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam, Cet. I, Jakarta
: Logos Wacana Ilmu, 1998 Echols, John M. dan Hassan sadly, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta : Gramedia,
1981 Ismail, Faisal., Paradigma Kebudayaan Islam, Studi Kritis dan Refleksi Historis,
Jogjakarta : Titian Ilahi Press, 1998 Ilyas, al-Qamus al-Ashry Injilis Arabi, Kairo : al-Maktabah al-Ashriyah, 1968 Nasir, Muhammad., Peranan Cendekiawan Muslim, Jakarta : DDII, 1978,
bandingkan dengan Delian Noor, Masalah Ulama Intelektual atau intelektual Ulama, Jakarta : Bulan Bintang, 1974 M
Nasution, Harun., Islam diTinjau dari Berbagai Aspeknya, Cet. 5, Jakarta : Universitas Indonesia (UI Press) 1985 M
Tilaar, H.A.R., Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Dalam perpektif Abad 21, Cet.IV, Magelang : Indonesia Tera, 2001
Sardar, Ziauddin., The Future of Muslim Civilization, London : Croom Helm, 1979 M
........., Information and The Muslim World a Strategy For The Twenty Fist Century, diterjenmahkan oleh A.E Priyono dan Ilyas Hasan, dengan judul
12 Faisal Ismail, Paradigma Kebudayaan Islam, Studi Kritis dan Refleksi Historis, (Jogjakarta :
Titian Ilahi Press, 1998) hal. 95 -96
PENGEMBANGAN SELF ESTEEM MELALUI PEMBELAJARAN KOOPERATIF
Robingatin
Abstract ;
Children with high self esteem are characterized by positive views towards themselves in some dimensions such as physical, academic, and social competence as the basis of their confidence, to make children appreciate themselves, bring sense of secure, and accepted by their friends or others. Children with high self esteem will judge their friends or others same as they are. Self esteem development by a teacher is done to serve children with respect, to help them success in school, to serve children without discrimination, threat, humiliation, and discouragement. Children self esteem development can be done through cooperative learning that teach cooperative principles and skills, establish community in the class, develop positive relationship among friends, tolerance towards the differences which simultaneously develop academic competence. Key Words : Pengembangan, Self Esteem, Pembelajaran Kooperatif A. PENDAHULUAN
Hakikat pendidikan adalah membantu terwujudnya aktualisasi diri baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, sebagaimana pandangan Scotter dkk bahwa pendidikan diarahkan pada pengembangan baik aspek pribadi maupun sosial agar menjadi anggota masyarakat dan berkembang secara individu demi terciptanya aktualisasi dan realisasi diri.1 Dengan kata lain bahwa melalui pendidikan dikembangkan potensi anak agar menjadi individu yang berkembang potensinya sehingga mencapai aktualisasi diri sebagai anggota dari sebuah masyarakat. Oleh karena itu pengembangan aspek sosio-emosional anak penting mendapat perhatian.
Pengembangan aspek sosio-emosi juga telah menjadi perhatian pendidikan afeksi sejak abad 20, yang menekankan pengembangan aspek sosio-personal, berbagai rasa atau feelings, emosi, moral, etik.2 Pendidikan afeksi ini lahir sebagai respon akan adanya berbagai tuntutan kebutuhan sosial termasuk issu rasial, obat-obat terlarang dan kejahatan pada remaja.3
Lahirnya pendidikan yang berbasis pada afeksi karena pendidikan yang yang mengembangkan aspek rasa, emosi dan moral etik selama ini belum mendapatkan tempat dalam kurikulum pendidikan.4 Secara idealnya kurikulum pendidikan, pada
Penulis adalah dosen tetap Jurusan Tarbiyah STAIN Samarinda, doktor lulusan Universitas
Negeri Jakarta 1 Richard D. Van Scotter et.al, Sosial of Education (New Jersey: Printice Hll Inc.,1985), hal. 106 2 Charles M. Reigeluth. (Editor), Instructional-Design Treories and Models (London: Lawrence
Elrbaum Association, 1999), hal. 486 3 Ibid. 4 Ibid.
semua jenjang pendidikan mengembangkan semua aspek fisik, emosi, sosial, dan kognitif5. Hal dikembangkan dan dirancang dengan menekankan pembelajaran sebagai proses interaktif.6
Pengembangan semua aspek anak bermuara pada tercapainya tujuan pendidik Pendidikan Nasional yakni terbentuknya warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Warga negara yang demokratis yang menjadi amanah Undang-undang menurut H.A.R.Tilaar antara lain dicirikan dengan adanya sikap toleran yang mengakomodasi berbagai jenis perbedaan dan saling mengisi antar anggota.7 Demikian pula ditandai kemampuan produktif bagi kemakmuran dirinya sendiri dan bagi kemakmuran bersama.
Kemampuan sebagai anggota yang produktif ini akan dimiliki manakala ada perasaan berharga yang hanya akan dimiliki mana kala seseorang atau sebuah masyarakat memiliki ketrampilan.8 Termasuk ketrampilan social dalam wujud kemampuan bekerja sama atau berkooperasi.
Berdasarkan dasar pemikiran tersebut maka penting dikembangkankan harga diri siswa melalui pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang akan meningkatkan harga diri adalah pembelajaran kooperatif. Melalui pembelajaran kooperatif anak mengembangkan kemampuan tanggung jawab pribadi, demikian pula dan anak terlibat dalam bentuk kegiatan bekerja sama yang memerlukan keterampilan sosial seperti membuat keputusan, membangun saling percaya, saling menghargai. Berbagai ketrampilan social yang berkembang melalui pembelajaran kooperatif ini pada gilirannya akan meningkatkan dan menngembangkan harga diri atau self-esteem anak.
Untuk itu penting juga pengembangan ketrampilan sosial pada anak sekolah dasar awal. Setidaknya ada 6 ketrampilan sosial yang perlu dikembangkan oleh pada guru yakni menolong anak mengembangkan empati, menolong anak agar menjadi anak yang pemurah, bersikap altruistic (rela berkorban) dan dapat berbagi dengan sesama, mendorong anak menjadi orang yang suka menolong atau prososial, membantu anak dapat merasakan bahagia atau senang dalam menolong teman, mengajarkan kepada anak bahwa setiap orang mempunyai hak yang harus dihargai, menekankan nilai-nilai kerjasama dan kompromi dibanding kompetisi serta mendorong anak menemukan keindahan dalam berteman.9
Harga diri sebagai syarat terwujudnya pribadi yang demokratis penting untuk dipersiapkan sejak anak berada di bangku sekolah dasar awal, karena harga diri juga
5 Sue Bredekamp, (editor), Developmentally Appropriate Practice in Early Childhood Programs Serving
Children From Birth through Age 8, (Washington, DC: National Association for the Education of Young Children, 1987),hal. 1
6 Ibid. hal.. 3 7 H.A.R. Tilaar, Multikulturalisme, Tantangan – tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi
Pendidikan Nasional, (Jakarta: Grasindo, 2004), hal. 199 8 Ibid. 9 Joanne Hendrich. The Whole Child Early Education For The Eighties. (Columbus: Ohio Charles
E. Merrill Publishing Company 1994), hal. 214-225
termasuk bagian dari komponen-komponen aspek perasaan moral (moral feeling).10 Hal ini didorong adanya realitas bahwa pada saat ini sangat sedikit anak yang datang ke sekolah dengan membawa respek ke orang dewasa. Para guru sering menyadari pentingnya harga diri dan mereka sering mendapatkan anak-anak masuk sekolah dengan harga diri yang rendah.11 Anak dengan harga diri yang relatif rendah memiliki pandangan yang negatif terhadap dirinya. Anak memandang dirinya secara pesimis. Hal ini akan menjadi kendala atau hambatan dalam berinterksi dengan orang lain. Anak akan merasa kurang aman dan tidak diterima orang lain.
Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang memiliki harga diri yang tinggi lebih kuat dengan tekanan dari anak sebayanya atau teman sebayanya dan memiliki kemampuan lebih mengambil keputusan dibanding dengan anak yang memiliki harga diri yang rendah. Apabila seseorang menghargai dirinya maka dia akan memperlakukan orang lain dengan cara yang positif dan jika dia memiliki harga diri rendah, maka dia berlaku kurang respek terhadap diri dan orang lain.12
B. PENTINGNYA ASPEK SELF-ESTEEM DALAM PEMBELAJARAN
Setidaknya ada enam ketrampilan sosial yang perlu dikembangkan oleh guru melalui pembelajaran yakni menolong anak mengembangkan empati, menolong anak agar menjadi anak yang pemurah, bersikap altruistic (rela berkorban) dan dapat berbagi dengan sesama, mendorong anak menjadi orang yang suka menolong atau prososial, membantu anak dapat merasakan bahagia atau senang dalam menolong teman, mengajarkan kepada anak bahwa setiap orang mempunyai hak yang harus dihargai, menekankan nilai-nilai kerjasama dan kompromi dibanding kompetisi serta mendorong anak menemukan keindahan dalam berteman.13
Harga diri sebagai syarat terwujudnya pribadi yang demokratis penting untuk dipersiapkan sejak anak berada di bangku sekolah dasar awal, karena harga diri juga termasuk bagian dari komponen-komponen aspek perasaan moral (moral feeling).14 Hal ini didorong adanya realitas bahwa pada saat ini sangat sedikit anak yang datang ke sekolah dengan membawa respek ke orang dewasa. Para guru sering menyadari pentingnya harga diri dan mereka sering mendapatkan anak-anak masuk sekolah dengan harga diri yang rendah.15 Anak dengan harga diri yang relatif rendah memiliki pandangan yang negatif terhadap dirinya. Anak memandang dirinya secara pesimis. Hal ini akan menjadi kendala atau hambatan dalam berinterksi dengan orang lain. Anak akan merasa kurang aman dan tidak diterima orang lain.
10 Ibid. hal.53 11 Thomas Lichona, Moral Development and Behavior, Theory, Reseach, and Sosial Issues (New
York:Holt, Rinehart and Winston, 1976), hal.109 12 Ibid, hal. 59. 13 Joanne Hendrich. The Whole Child, hal. 214-225 14 Ibid. hal..53 15 Lichona, Moral, hal. 109
C. HAKEKAT SELF-ESTEEM 1. Pengertian Self-Esteem
Harga diri atau dalam istilah psikologinya self-esteem merupakan pembahasan penting dalam psikologi, karena terkait dengan aspek emosional yang merupakan salah satu dimensi manusia.16 Menurut Coopersmith harga diri adalah penilaian umum tentang diri sendiri yang berkaitan dengan kemampuan diri, memiliki sesuatu yang bernilai, dan bernilai dalam pandangan orang lain.17 Sedangkan menurut Santrock harga diri ialah dimensi evaluatif global dari diri. Harga diri juga diacu sebagai nilai diri atau citra diri. Istilah haraga diri sering digunakan secara bergantian dengan dengan self-concept, yakni suatu pengertian yang mengacu pada evaluasi bidang spesifik dari diri sendiri. Kedua pengertian tersebut tidak didefinisikan secara berbeda dengan jelas.18
Adapun menurut Laura E. Berk, harga diri merupakan bagian dari self-concept.19 Sedangkan menurut Branden, harga diri terdiri dari dua komponen yakni self-efficasy dan self respect.20 Senada dengan pandangan ini, menurut Robert S. Feldman harga diri adalah penerimaan diri seseorang akan dirinya sendiri atau tingkatan penilaian orang tentang harga diri.
Seseorang yang menghargai dirinya apa adanya dikatakan memiliki harga diri yang tinggi, sedangkan apabila seseorang memiliki rasa kurang respek terhadap dirinya atau menolak dan memandang negative terhadap dirinya menunjukkan harga diri rendah.21
Menurut Jeffrey Trawick-Smith, harga diri yang positif atau tinggi juga ditunjukkan melalui perasaan positif atau penilaian positif terhadap diri sendiri. Menurut Jeffrey, dimensi harga diri meliputi perasaan mampu (competence), perasaan diterima secara social (social acceptance), perasaan mampu mengontrol diri atau (feeling of control), perasaan akan nilai moral (feeling of moral self-woth).22 Harga diri, ditunjukkan dari perasaan kompeten dalam satu bidang spefisik, misal dalam bidang matematik atau sain dan bukan pada membaca. Sebagian anak menunjukkan perasaan diterima oleh teman tetangga, tetapi tidak merasa diterima oleh teman di sekolahnya. Sedangkan perasaan mampu mengontrol diri (feeling of control) atau yang disebut para psikolog dengan locus of control ditunjukkan melalui kerja keras dan kemampuan menyelesaikan problem yang akan membawa keberhasilan. Adapun perasaan nilai
16 Matthew Mckay and Patrick Fanning, Self-Esteem (USA: New Harbinger Publications, Inc,
2000), hal. 1 17 Camille B. Wortman, at.all, Psychology, (New York, Alfred A. Knopf), hal. 387 18 John W. Santrock, Live-span Development, Achmad Chusairi, (pent.), (Jakarta: Erlangga), hal.
.357 19 Laura E. Berk, Child Development, (Boston: Allyn and Bacon, 1989), hal. 469. 20 Nathaniel Branden, Six Pillars of Self-esteem, (New York: Bantan,1994), hal. .27 21 Robert S.Feldman, Adjustment, Aplying Psycolgy in a Complex World, (USA:McGraw-Hill,Inc,
1989), hal..12 22 Jeffrey Trawick-Smith, Early Childhood Development, A Multicultural Perspective, (USA: Merrill
Prencice Hall,2003),hal.. 417 -420
moral diri (feeling of moral self-worth) ditunjukkan melalui kemampuan anak menilai tentang kebaikan. 23
Para psikolog dari berbagai aliran memandang bahwa penilaian diri merupakan suatu hal yang sangat penting. Carl Rogers memandang bahwa penilaian tentang diri yang tidak rasional merupakan sumber dari kekacauan psikologis. Menurut Rogers, seseorang memiliki harga diri rendah jika terdapat jarak antara apa yang dia harapkan dengan apa yang senyatanya. Bandura juga menekankan pentingnya perasaan mampu (self-efficacy) dalam pembentukan perilaku seseorang. Demikian pula Karen Horney menekankan pentingnya harga diri sebagai dasar pengembangan kepribadian yang sehat.24 Menurut Maslow (1962) merupakan salah satu dari 4 kebutuhan psikis manusia yakni kebutuhan akan survival, rasa aman, afiliasi dan esteem. Esteem dibedakan esteem dari orang lain dan esteem yang berasal dari diri sendiri atau perasaan diri mampu (the individual’s sense of competence or mastery).25
2. Perkembangan Self-Esteem Perkembangan self-esteem anak muncul dari pandangan seseorang terhadap
diri sendiri dan pengalaman yang dilalui anak merupakan dasar konsep diri dan harga diri. Jika seorang anak diperlakukan dengan kehangatan dan cinta, konsep dasar yang mungkin muncul adalah perasaan positif terhadap diri anda sendiri. Jika seorang anak mengalami penyia-nyiaan atau penolakan, yang tertanam adalah bibit penolakan diri masa mendatang. Coopersmith (1967) menemukan bahwa anak-anak khususnya anak laki-laki dengan self-esteem tinggi memiliki orang tua yang menerima dirinya, penuh kasih sayang dan memperhatikan anak serta senantiasa menerapkan peraturan secara hati-hati dan konsisten menetapkan standar tinggi. Anak-anak dengan harga diri tinggi berlaku lebih demokratis dalam berinteraksi dengan temannya.26
Anak-anak mengembangkan konsep diri dan harga diri pada awal-awal kehidupan dan menjadi menetap pada saat mereka berkembang secara sosial. Pada saat awal kehidupannya anak sedang berkembang berbagai perasaan yang mengarah kepada identitas dirinya antara lain perasaan akan keberadaannya saat anak merasakan secara bertahap berpisah dengan orangtua. Anak juga mulai mengenal siapa orang lain dan mengenali bahwa orang lain berbeda dengan dia. Anak juga berkembang harga dirinya atau self-worth walau anak belum mampu mengutarakannya secara verbal, namun anak menunjukkan kesetujuannya, kekecewaannya, ketakutan, dan kepuasaannya melalui suara, ekspresi wajah dan bahasa tubuh secara umum.27
23 Ibid. hal. .418 24 Camilla B. Wortman, Psychology, hal. 387 25 Thomas Lichona, Moral Development, hal.160. 26 Jo Ann Brewer, Introduction to Early Childhood Education, Preschool through primary Grade,
(Boston, Pearson, 2007), hal. .22 27 Ibid. hal.. 203
3. Ciri-ciri Anak dengan Self-Estem Tinggi Anak dengan harga diri yang tinggi memandang dirinya positif dalam beberapa
dimensi seperti kecakapan fisik, kemampuan akademik, dan sosial. Anak dengan harga diri tinggi akan memandang dirinya secara positif, misal dia menarik secara fisik, mampu berenang, punya teman banyak dan baik. Perasaan positif anak dalam memandang totalitas dirinya ini akan menjadi sumber kepercayaan dirinya, membuat anak menghargai dirinya dan akan mendatangkan rasa aman dan diterima oleh teman atau orang lain. Anak dengan harga diri yang tinggi, akan menilai orang lain atau teman lain sama dengan dirinya. Maka anak akan tidak merasa ada perbedaan dengan teman lain dan akan menghargai teman atau orang lain serta menerima perasaan orang lain. Penerimaan akan dirinya dan orang lain memungkinkan anak dapat menyelesaikan konfiik yang mereka alami baik dengan dirinya atau dengan orang.
Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang memiliki harga diri yang tinggi lebih kuat dengan tekanan dari anak sebayanya atau teman sebayanya dan memiliki kemampuan lebih mengambil keputusan dibanding dengan anak yang memiliki harga diri yang rendah. Apabila seseorang menghargai dirinya maka dia akan memperlakukan orang lain dengan cara yang positif dan jika dia memiliki harga diri rendah, maka dia berlaku kurang respek terhadap diri dan orang lain.28
Anak-anak mengembangkan harga dirinya pada awal-awal kehidupan dan menjadi menetap pada saat mereka berkembang secara sosial. Pada saat awal kehidupannya anak sedang berkembang berbagai perasaan yang mengarah kepada identitas dirinya antara lain perasaan akan keberadaannya. Pandangan seseorang terhadap
D. PEMBELAJARAN KOOPERATIF UNTUK MENGEMBANGKAN
SELF-ESTEEM Pengembangan self-Esteem anak dapat dilakukan melalui pembelajaran yang
berbasis pada kooperatif atau Cooperatif Learning atau Cooperative Play. Melalui pembelajaran atau bermain kooperatif, anak dapat mengembangkan kerjasama yang menghasilkan keuntungan bagi diri dan orang lain, memperkirakan tanggung jawab pribadi dan anak terlibat dalam bentuk kegiatan bekerja sama yang memerlukan keterampilan sosial seperti membuat keputusan, membangun saling percaya dalam tim.29
Pembelajaran yang disebut juga instruksional adalah usaha mengelola lingkungan dengan sengaja agar seseorang membentuk diri secara positif dalam kondisi tertentu.30 Cooperative learning atau pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran dengan cara menciptakan kondisi bekerja sama yang ditujukan untuk pengetahuan, konsep, skill dan pemahaman untuk membantu siswa memperoleh prestasi akademik dan ketrampilan dalam berinteraksi sosial seperti toleransi dan menghargai perbedaan dan
28 Ibid, hal. 59. 29 Ibid. hal. 274 30 Ibid, hal..529
pengembangan ketrampilan sosial.31 Cooperatif learning dilakukan dengan pengelompokan kecil yang masing-masing siswa dari tingkat kemampuan berbeda menggunakan kegiatan belajar yang bermacam-macam untuk meningkatkan hasil belajar. Setiap anggota kelompok tidak hanya bertanggungjawab untuk mempelajari apa yang dipelajari, tetapi juga membantu teman sekelompoknya dalam belajar sehingga dapat menciptakan suatu prestasi. Siswa belajar melalui penugasan sampai seluruh anggota kelompok berhasil memahami dan melengkapinya. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning di dilakukan dengan kelompok kecil dimana para siswa dapat merepresentasikan hasil belajar kelompok kepada kelompok lainnya secara bergantian.32
Pembelajaran kooperatif mendatangkan beberapa keuntungan yakni: mengajarkan nilai-nilai bekerjasama, membangun komunitas dalam kelas, mengajarkan ketrampilan dasar hidup, meningkatkan prestasi akademik dan perilaku positif terhadap sekolah serta menjadi alternatif mengatasi drop out, demikian pula dapat menekan munculnya dampak negatif adanya kompetisi.33
Salah satu aspek yang penting dikembangkan dalam pembelajaran kooperatif adalah perilaku kerjasama dan mengembangkan hubungan positif antar teman, toleransi terhadap perbedaan yang secara simultan akan mengembangkan kemampuan akademik. Sebuah studi terhadap pembelajaran kooperatif menyimpulkan bahwa dalam semua tingkat dan berbagai pelajaran yakni seni berbahasa, mengeja, geograpi, ilmu sosial, sain, matematika, bahasa engris sebagai bahasa kedua, membaca dan menulis, mampu meningkatkan kemampuan akademik. Studi ini dilakukan baik di daerah perkotaan dan pedesaan dan semi perkotaan di Negara Amerika, Israel, Nigeria dan Jerman.34
Dalam belajar kooperatif tidak hanya mempelajari materi saja tetapi siswa juga mempelajari ketarampilan kooperatif dan kolaboratif yang berfungsi melancarkan dalam bekerjasama dalam kelompok. Peranan hubungan kerja dapat dibangun dengan membagi tugas anggota kelompok selama kegiatan berlangsung.
Menurut Johnson & Johnson tidak semua kerja kelompok bisa dianggap belajar kooperatif. Untuk mencapai hasil yang maksimal lima unsur model belajar kooperatif harus ditekankan: 35 (a) saling ketergantungan positif, (b) tanggung jawab perseorangan, (c) tatap muka, (d) komunikasi antar anggota, dan (e) evaluasi proses kelompok.
Strategi belajar pembelajaran kooperatif didasarkan pada fiisafat Dewey, Psikologi Behaviorisme, psikologi kognitif, dan psikologi sosial. Pembelajaran
31 Richard I.Arends, Learning to teach, (New York: McGraw-Hill,2004), hal. 356 32 Microoft R Encarta 2006. C 1993-2005 Microsoft Corporation.All right reserve. 33 Thomas Lichona. Educating for Character. How Our Schools can Teach Respect and Responsibility,
(New York: Bantan Books, 1991), hal. 187-188. 34 Arends, Learning, hal.. 360 35 D.W Jhohnson & R.T.Jhonson, Cooperatif Learnng in Te Classroom, (Minneapolis: Interaction
Book Company, 1984), hal. 10
kooperatif yang pertama kali diilhami oleh John Dewey dan Thelen menjadikan kelas sebagai miniatur demokrasi yang kemudian dikembangkan oleh Johson dan Johson.36
Setidaknya ada 3 teori secara umum yang memandu penelitian tentang cooperative, yakni cognitive-developmental (perkembangan kognitif), behavioral dan interpendensi.37 Cooperatif learning sejalan dengan teori perubahan. Anak akan mengalami proses belajar apabila anak diberi kesempatan untuk mengekspresikan ide-ide dan nilai-nilai baik melalui kata-kata atau perbuatan dan mereka melihat apa yang mereka alami mereka juga memerlukan reaksi atau tanggapan tidak hanya dari guru melainkan juga dari perannya atau orang lain. Anak akan lebih mudah mengingat suatu konten atau materi pembelajaran manakala mereka menghubungkannya dengan pengetahuan yang lain ketika mereka bertanya, menjelaskan atau menyimpulkan. Diskusi dan pengalaman-pengalaman tersebut memberi tempat adanya saling menghormati dan mendukung. Nilai-nilai tidak semata-mata berubah hanya dengan mendengar secara pasif seperti mendengar ceramah. Perubahan nilai akan terjadi dalam situasi dimana baik guru dan murid dan saling mendengar dan saling belajar satu dengan lainnya.38
Sejalan dengan pernyataan tersebut, menurut Keachie bahwa Cooperatif learning sering berdampak positif terhadap perilaku dan nilai-nilai. Kooperatif atau kerjasama sendiri merupakan nilai yang sangat penting dalam budaya kita dan keberhasilan dalam belajar bekerjasama dengan teman lain dalam satu proyek atau pengalaman belajar yang lain, akan berdampak positif pada kemampuan bekerja sama anak.39
Harga diri berkaitan dengan kemampuan diri anak baik dalam bidang akademik, sosial atau ketrampilan lain yang yang menjadikan anak memiliki sesuatu yang bernilai dan bernilai dalam pandangan orang lain. Dalam hal ini Berbagai pengalaman yang diperoleh anak melalui interaksi dengan teman sebaya dalam pembelajaran kooperatif akan meningkatkan kemampuan anak baik secara akademis maupun dalam perolehan kerampilan sosial seperti kerjasama, prososial, toleransi, berempati, kontrol diri yang akan melahirkan rasa puas dan pada gilirannya akan meningkatkan harga diri anak. Prestasi akademik dan ketrampilan sosial akan membawa kepada perubahan rasa mampu anak, rasa berharga diri dan rasa bernilai anak.
E. KESIMPULAN Dari pembahasan terhadap pengembangan self-esteem anak Sekolah Dasar tersebut dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Dimensi self-esteem atau harga diri meliputi perasaan mampu (competence), perasaan diterima secara sosial (social acceptance), perasaan mampu mengontrol diri atau (feeling of control), perasaan akan nilai moral (feeling of moral self-woth).
2. Anak yang dengan self-esteem atau harga diri yang tinggi dicirikan dengan adanya pandangan positif terhadap dirinya dalam beperapa dimensi seperti
36 Arends, Learning, hal. 356 37 David W. Johnson dan Frank P. Johnson, Joining Together, Group Theory and Group Skills
(Boston: Allyn and Bacon, 1997), hal..97. 38 Wilbert J.McKeachie,at.all. Teaching Tip (Toronto:D.C.Heath and Company,1994), hal. 383 39 Ibid
kecakapan fisik, kemampuan akademik, dan sosial yang akan menjadi sumber kepercayaan dirinya, membuat anak menghargai dirinya dan akan mendatangkan rasa aman dan diterima oleh teman atau orang lain. Anak dengan harga diri yang tinggi, akan menilai orang lain atau teman lain sama dengan dirinya. Maka anak akan tidak merasa ada perbedaan dengan teman lain dan akan menghargai teman atau orang lain serta menerima perasaan orang lain.
3. Pengembangan harga diri oleh guru dilakukan dengan melayani anak dengan respek, membantu mereka berhasil di sekolah, melayani anak-anak dengan menghindari pilih kasih, ancaman, memalukan atau melakukan dan merendahkan harga diri.
4. Pengembang self-esteem anak dapat dilakukan melalui pembelajaran kooperatif yang mengajarkan nilai-nilai bekerjasama, membangun komunitas dalam kelas, mengajarkan ketrampilan kerjasama, mengembangkan hubungan positif antar teman, toleransi terhadap perbedaan yang secara simultan akan mengembangkan kemampuan akademik.
BIBLIOGRAFI Arends, Richard I., Learning to teach, New York: McGraw-Hill,2004 Gardner, Judith Krieger., Reading in Developmental Psychology, Boston, Litle, Brown and
Company,1995 Berk, Laura E., Child Development, Boston: Allyn and Bacon, 1989
Mckay, Matthew., and Patrick Fanning, Self-Esteem, USA: New Harbinger Publications, Inc, 2000
Branden, Nathaniel., Six Pillars of Self-esteem, New York: Bantan,1994 Bredekamp, Sue., (editor), Developmentally Appropriate Practice in Early Childhood Programs
Serving Children From Birth through Age 8, (Washington, DC: National Association for the Education of Young Children, 1987
Brewer, Jo Ann, Introduction to Early Childhood Education, Preschool through primary Grade, Boston, Pearson, 2007
Feldmen, Robert S., Adjustment, Aplying Psycolgy in a Complex World, USA:McGraw-Hill,Inc, 1989
Jhohnson, D.W., & R.T.Jhonson, Cooperatif Learnng in Te Classroom, (Minneapolis: Interaction Book Company, 1984
Lichona, Thomas., Moral Development and Behavior, Theory, Reseach, and Sosial Issues, New York:Holt, Rinehart and Winston, 1976.
Reigeluth Charles M.. (Editor), Instructional-Design Treories and Models (London: Lawrence Elrbaum Association, 1999
Santrock, John W., Live-span Development, Achmad Chusairi, (pent.), Jakarta: Erlangga,2003
Scotter, Richard D. Van., et.al, Sosial of Education , New Jersey: Printice Hll Inc.,198
Smith, Jeffrey Trawick., Early Childhood Development, A Multicultural Perspective, USA: Merrill Prencice Hall,2003
Tilaar., H.A.R., Multikulturalisme, Tantangan – tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional, Jakarta: Grasindo, 2004
Wortman, Camille B., at.all, Psychology, New York: Alfred A. Knopf