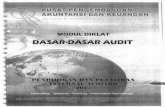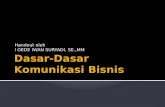Dasar-dasar Ekologi Pengenalan Ekosistem Waduk
Transcript of Dasar-dasar Ekologi Pengenalan Ekosistem Waduk
ACARA 5
PENGENALAN EKOSISTEM WADUK
I. TUJUAN
1. Mempelajari macam-macam ekosistem.
2. Mengetahui struktur dan komponen pembentuk ekosistem.
II. TINJAUAN PUSTAKA
Kelestarian ekosistem merupakan suatu hal yang harus selalu dipertahankan agar
tercipta suatu keseimbangan antara alam dengan makhluk hidup. Interaksi yang ditimbulkan
dari makluk hidup terhadap alam, haruslah interaksi yang saling menguntungkan. Hal
tersebut dikarenakan apabila alam hanya selalu dimanfaatkan tanpa memperhatikan
kelestarian ekosistem didalamnya, maka dikhawatirkan alam tidak lagi mampu menyediakan
pemenuhan kebutuhan makhluk hidup.
Manusia sebagai makhluk hidup yang berakal mempunyai potensi paling besar
dibandingkan hewan ataupun makhluk lainnya dalam rangka mempertahankan ekosistem
alam. Bahkan manusia mampu menciptakan ekosistem buatan sebagai alternatif baru dalam
rangka mencukupi kebutuhan manusia yang semakin hari semakin meningkat. Meskipun
keberadaan manusia dianggap sebagai mkhluk yang potensial dalam menjaga kelestarian
ekosistem, namun tidak sedikit manusia yang hanya memanfaatkan kekayaan alam tetapi
tidak memberikan timbale balik yang postif bagi alam. Hal yang demikian itulah yang
sekarang ini menjadi masalah pelik yang sulit dipecahkan, bahkan keberadaan hutan sebagai
paru-paru duniapun sekarang ini sudah mulai terancam kelestariannya karena adanya
kebakaran ataupun penebangan liar.
Ekosistem adalah satuan fungsional dasar ekologi karena terdiri dari organisme biotik
maupun abiotik. Dari segi fungsional, ekosistem dapat dianalisir dari segi sirkuit-sirkuit
energi, rantai makanan, pola keanekaragaman dalam ruang dan waktu, daur makanan
(biogeokimia), perkembangan dan evolusi serta pengendalian (Odum, 1983).
Ekosistem adalah hubungan timbal balik yang kompleks antara organisme dan
lingkungannya baik yang hidup (biotis) maupun yang tidak hidup (abiotis) yang secara
bersama-sama membentuk suatu sistem ekologi. Suatu organisme tidak akan dapat hidup
sendiri tanpa berinteraksi dengan organisme lain atau lingkungan hidupnya. Dengan
demikian untuk kelangsungan hidup suatu organisme akan bergantung pada kehadiran
organisme lain dan sumber daya alam yang ada di sekitarnya untuk keperluan pangan,
perlindungan, pertumbuhan, perkembangbiakan, dan sebagainya. Hubungan antara suatu
organisme tersebut sangat rumit dan sifatnya timbal balik (Cahyo, dan Muhartini, 1998).
Suatu ekosistem tersusun dari organisme hidup di dalam suatu area ditambah dengan
keadaan fisik yang mana saling berinteraksi. Karena tidak ada perbedaan yang tegas antara
ekosistem maka objek pengkajian harus dibatasi atas daerah dan unsur penyusunnya.
Kegunaan dari pemikiran dalam ekosistem adalah saling keterkaitan antara satu dengan hal
yang lain, saling ketergantungan, dan hubungan sebab akibat yang kesemuanya itu
membentuk suatu rantai kehidupan yang berkesinambungan (Clapham et al., 1973 ).
Dalam suatu ekosistem, terdapat beberapa unsur penyusun ekosistem yang berupa
unsur biotik, dan abiotik. Lingkungan biotik disusun organisme sejenis disebut populasi, yang
saling berinteraksi dengan populasi lain sebagai komunitas dan berinteraksi dengan
lingkungan abiotik membentuk ekosistem. Sedangkan tempat hidup organisme disebut
habitat (Odum , 1959). Unsur biotik masih terbagi lagi menjadi dua macam, yaitu organisme
autotrof, dan heterotrof. Yang dimaksud dengan organisme autotrof adalah organisme yang
mampu membuat/mensintesis makanannya sendiri, contohnya adalah tanaman. Sedangkan
organisme heterotrof adalah organisme yang tidak mampu membuat/mensintesis
makanannya, contohnya adalah hewan. Pengurai merupakan organisme heterotrof yang
menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati (bahan organik kompleks).
Organisme pengurai tersebut akan melepaskan bahan-bahan yang sederhana yang dapat
digunakan lagi oleh produsen. Yang termasuk adalah bakteri jamur dan lain-lain (Warsito dan
Setyawan , 2000 ). Unsur abiotik adalah faktor utama dalam ekosistem setelah Unsur biotik,
karena unsure ini bertugas untuk menciptakan keadaan yang diperlukan oleh mahluk hidup
seperti cahaya, suhu, topografi, dan lain sebagainya (Wagnet et. al.,, 2003).
III. METODOLOGI
Praktikum Dasar-Dasar Ekologi yang berjudul Pengenalan Ekosistem Waduk
dilaksanakan di Waduk Jombor, Klaten, Yogyakarta, pada hari Minggu, 9 Maret 2014. Alat-
alat yang digunakan adalah kamera. Sedangkan, bahan-bahan yang digunakan adalah
organisme-organisme dan komponen-komponen waduk yang berada pada ekosistem waduk.
Praktikum ini dimulai dengan diamatinya tanaman dan hewan yang berada dalam
ekosistem waduk, kemudian masing-masing spesies diidentifikasikan. Kemudian diamati
pula komponen-komponen pembentuk waduk tersebut, sehingga dapat dibuat jejaring
makanan, arus energi dan daur materi yang terjadi dalam ekosistem waduk tersebut.
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Ekosistem Waduk Jombor merupakan ekosistem buatan hasil transformasi atau alih
fungsi ekosistem rawa yang kemudian diubah dan dijadikan waduk. Secara alami, komponen
ekosistem yang ada sebagian besar masih sama seperti ekosistem rawa, namun semakin lama
keaslian ekosistem rawa berubah menjadi ekosistem waduk (buatan), jadi dapat dikatakan
bahwa ekosistem Waduk Jombor berbeda dengan ekosistem waduk pada umumnya karena
ada campuran antara ekosistem waduk dan rawa.
Rawa Jombor merupakan sebuah rawa yang terletak di tengah Desa Krakitan. Rawa
ini dikelilingi oleh bukit-bukit yang sebagian besar merupakan pegunaungan kapur. Rawa
Jombor berjarak kurang lebih 8 km dari kota Klaten. Rawa ini memiliki luas 198 ha dengan
kedalaman meencapai 4,5 m dan meemiliki daya tampung air 4 juta m3. Tanggul yang
mengelilingi rawa ini sepanjang 7,5 km dengan lebar tanggul 12 m.
Daerah Rawa Jombor dahulu sebenarnya merupakan dataran rendah yang berbentuk
cekungan luas dan dikelilingi oleh barisan pegunungan. Hal ini menyebabkan dataran rendah
tersebut sering tergenang air, baik pada saat musim hujan maupun musim kemarau. Daerah
tersebut dinamakan Rawa Jombor karena daerah tersebut sering tergenang air sehingga
disebut rawa dan terletak di Desa Jombor yang kini berubah menjadi Desa Krakitan.
Genangan air ini akan semakin tinggi saat musim hujan karena dari sebelah barat laut
terdapat sungai yang bernama Kali Ujung dan kali Dengkeng. Kedua sungai tersebut selalu
meluap saat musim hujan dan selalu mengarah ke Rawa Jombor. Luapan air ini membuat
Rowo Jombor semakin meluas dan menggenangi rumah warga serta sawah yang berada di
sekelilingnya sehingga banyak warga yang terpaksa dipindahkan ke tempat yang lebih aman
di tepi rawa atau tegalan di sekitarnya.
Pada tahun 1901, Sinuwun Paku Buwono ke-X bersama dengan pemerintah belanda
mendirikan pabrik gula Manisharjo di daerah Pedan, Klaten. Dibukanya pabrik gula ini
membuat seluruh lahan pertanian di daerah Pedan tersebut ditanami dengan tanaman tebu.
Luasnya lahan yang digunakan untuk perkebunan tebu tersebut meningkatkan jumlah
kebutuhan air untuk irigasi. Sehingga Sinuwun Paku Buwono ke-X dan Pemerintah Belanda
yang mengetahui keberadaan Rawa Jombor dengan jumlah air yang melimpah berencana
untuk membuat saluran irigasi dari Rawa Jombor menuju areal perkebunan tebu tersebut.
Pembangunan saluran irigasi tersebut dimulai pada tahun 1917 dengan cara membuat
terowongan sepanjang 1 km menerobos pegunungan yang mengelilingi rawa serta talang air
di atas kali Dengkeng. Pekerjaan ini akhirnya selesai pada tahun 1921 dan setiap tahun
Sinuwun Paku Buwono ke-X selalu mengunjungi Rawa Jombor walaupun hanya untuk
sekedar naik perahu atau melihat pemandangan.
Pada saat penjajahan Jepang, pabrik gula Manisharjo yang sebelumnya dikelola oleh
pemerintah Belanda menjadi bangkrut. Pada tahun 1943-1944, oleh pemerintah Jepang, Rawa
Jombor kemudian dijadikan waduk dengan dibangunnya tanggul di sekeliling rawa dengan
memanfaatkan tenaga kerja paksa (romusha). Sebelum dibangun tanggul, luas Rawa Jombor
sekitar 500 hektar sementara setelah dibangun tanggul dengan lebar 5 m maka luasnya
menjadi 180 hektar.
Setelah penjajahan Jepang berakhir Rawa Jombor tetap dimanfaatkan sebagai waduk
untuk menampung air irigasi bahkan pada tahun 1956, pemerintah kota Klaten menetapkan
Rawa Jombor sebagai tujuan wisata dengan melakukan pembangunan tempat peristirahatan
untuk pengunjung. Pada tahun 1967-1968, setelah adanya pemerintahan Orde Baru,
pemerintah kota Klaten memanfaatkan para tahanan politik (tapol) untuk melakukan
perbaikan Rawa Jombor. Perbaikan tersebut dilakukan dengan memperlebar tanggul yang
awalnya hanya 5 meter menjadi 12 meter. Pekerjaan tersebut selesai dalam 7 bulan dengan
menyerap tenaga kerja tapol sebanyak 1700 orang.
Rawa Jombor berfungsi untuk irigasi, budidaya ikan, pariwisata dan pada tahun 1996
mulai dimanfaatkan sebagai tempat warung makan apung. Rawa Jombor dapat mengairi
sawah yang berada di sekitar rawa. Budidaya ikan dengan menggunakan karamba sudah ada
sebelum berdirinya warung apung dan keberadaan karamba ini memberikan kontribusi yang
penting untuk menyediakan ikan segar bagi masyarakat. Keindahan alam di Rawa Jombor
banyak menarik perhatian masyarakat sehingga banyak wisatawan local maupun manca yang
berkunjung.
Dalam suatu ekosistem, tentu terdapat dua komponen penyusun, yaitu komponen
biotik dan abiotik. Komponen abiotik yang ditemukan di daerah ekosistem Waduk Jombor
adalah air, batu-batuan, tanah (dasar waduk), udara, suhu, sinar matahari dan komponen tak
hidup lainnya. Dalam ekosistem waduk, air merupakan komponen biotik yang paling
berpengaruh karena hampir semua unsur ekosistem ini berada di air meliputi tumbuhan,
beberapa jenis hewan, dan dekomposernya. Warna air pada waduk jombor adalah Jernih
kekuning-kuningan. Warna dari air terbentuk dari susunan atau zat yang terkandung di dalam
air tersebut. Untuk kandungan air dapat dianalisa secara laboratoris agar didapatkan hasil
yang lebih akurat. Batu-batuan dan tanah yang terdapat di Waduk Jombor terletak di bagian
dasar waduk yang sulit untuk diamati karena kedalaman waduk yang mencapai 4,5 meter
sehingga tidak dimungkinkan pengambilan sampel. Namun diasumsikan bahwa tanah yang
berada di dalam waduk jombor masih seperti rawa dikarenakan memang dahulunya waduk
ini berupa rawa. Penambahan komponen atau volume tanah di dasar waduk juga terjadi
karena pengendapan partikel-partikel tanah yang terbawa masuk ke dalam waduk tersebut.
Karena waduk merupakan ekosistem yang jenuh dengan air, maka tanah di dasar waduk
berupa lumpur (campuran tanah dan air) yang dapat dilihat ketika kita mengambil tongkat
yang digunakan untuk mendorong kapal bambu atau getek maka terlihat sisa-sisa lumpur
yang masih menempel. Intensitas dan kualitas cahaya matahari memengaruhi proses
fotosintesis. Air dapat menyerap cahaya sehingga pada lingkungan air, fotosintesis terjadi di
sekitar permukaan yang terjangkau cahaya matahari. Iklim adalah kondisi cuaca dalam
jangka waktu lama dalam suatu area. Iklim makro meliputi iklim global, regional dan lokal.
Iklim mikro meliputi iklim dalam suatu daerah yang dihuni komunitas tertentu.
Komponen biotik yang ditemukan di Waduk Jombor adalah, kangkung air (Ipomoea
aquatica), eceng gondok (Eichornia crassipes), dan lumut dinding. Kemudian hewan yang
mendiami waduk itu adalah Ikan mas (Cyprinus carpio), Ikan Sepat (Trichogaster
trichopterus), Ikan Nila (Oreochromis niloticus), dan Ikan gabus (Channa striata). Dan selain
hewan yang ada dalam air, ada beberapa hewan di luar ekosistem waduk ikut mempengaruhi
keseimbangan ekosistem tersebut, antara lain keong mas (Pomacea canaliculata), belalang
(Dissosteira carolina), capung (Neurothemis sp), bebek, burung kuntul, dan manusia.
Dalam sebuah ekosistem dikenal istilah arus energi dan daur materi. Arus energi ialah
arus yang menggambarkan perpindahan energi dari sinar matahari menuju prdusen, kemudian
dari produsen menuju konsumen, lalu dari konsumen menuju dekomposer, dan pada akhirnya
dekomposer mengeluarkan energi dalam bentuk lain. Setiap energi yang berpindah dari satu
tingkatan trofik ke trofik lainnya akan mengeluarkan entropi, dengan jumlah maximum 10%.
Entropi adalah energi yang dikeluarkan dalam bentuk panas yang sudah tidak dapat
digunakan lagi. Perpindahan energi antar organisme disebut arus karena tidak siklis, yaitu
berasal dari matahari tetapi tidak kembali lagi untuk siklis ke matahari. Sedangkan
perpindahan materi disebut daur, hal ini disebabkan karena materi tersebut mengalami
perpindahan siklis, yaitu berasal dari tumbuhan kemudian akan beputar kembali menuju
tumbuhan. Tumbuhan menggunakan materi tersebut setelah diuraikan menjadi komponen
abiotik di dalam tanah. Materi berpindah dari suatu organisme ke organisme lain akibat
proses makan-dimakan, kemudian organisme mati dan diuraikan oleh dekomposer yang akan
menghasilkan bahan mineral siap pakai yang dapat dimanfaatkan tumbuhan hijau untuk
berfotosintsesis. Demikian seterusnya. Sehingga aliran ini tidak pernah terputus.
Arus Energi
Daur Materi
Di dalam ekosistem waduk, terdapat proses makan-dimakan. Kegiatan tersebut akan
membuat suatu rantai makanan. Rantai makanan adalah suatu skema makhluk hidup yang
menggambarkan peristiwa makan dan dimakan. Peristiwa rantai makan pasti terjadi di setiap
ekosistem begitu pula di waduk jombor, antar unsur biotiknya pasti terjadi peristiwa makan
dan dimakan yang dapat digambarkan dalam suatu rantai makanan sebagai berikut:
Produsen
Konsumen Primer
Konsumen Sekunder
Konsumen Tersier
Dekomposer
Produsen Konsumen Dekomposer
Rantai Makanan
Dari rantai makanan tersebut dapat dikembangkan manjadi sebuah jaring-jaring
makanan, sebagai berikut:
Jaring-Jaring Makanan
Seperti yang kita ketahui, bahwa ekosistem mempunyai tingkatan trofik, yaitu
produsen konsumen, dan dekomposer. Yang bertindak sebagai produsen adalah tumbuhan,
karena tumbuhan termasuk organisme autotrof, yyaitu organisme yang mampu membuat atau
Tumbuhan Air
Ikan Kecil Ikan Besar
Burung Kuntul
Dekomposer
mensintesis makanannya sendiri. Yang bertindak sebagai konsumen tingkat I adalah
serangga, keong mas, dan ikan kecil. Kemudian yang menduduki konsumen tingkat II adalah
burung kuntul, bebek, manusia, dan ikan besar. Pada konsumen tingkat III diduduki oleh
manusia. Dan pengurai atau dekomposer yang tidak dapat kami amati.
V. KESIMPULAN
1. Ekosistem mmemiliki berbagai macam jenis, diantaranya adalah ekosistem daratan
(teresstrial) dan ekosistem perairan (aquatic).
2. Komponen pemmbentuk ekosistem adalah komponen biotik dan abiotik. Dalam
ekosistem waduk ini, yang termasuk dalam komponen biotik adalah kangkung air,
ikan, dan lain-lain. Sedangkan yang termasuk dalam komponen abiotik adalah batu,
tanah, iklim, cahaya matahari, dan lain-lain.
DAFTAR PUSTAKA
Abdurahman, D. Dan Aprillia. 2008. Biologi Kelompok Pertanian dan Kesehatan untuk
Kelas XI SMK. Grafindo Media Pratama, Bandung.
Cahyo, S. dan Muhartini. 1998. Ekologi Pertanian. Universitas Terbuka, Jakarta.
Clapham, W.B. 1973. Natural Ecosystem. Mac Millian Publishing Co, Inc, New York.
Odum, H.T. 1959. Fundamentals of Ecology, W. B. Sounders, Philadelpia.
Wagenet, R. J., R. R. Rodriguez, W. F. Cambel and D. L. Turner. 2003. Fertilizer effect on
garden plants. Agronomy Journal 3 : 160 - 164.
Warsito dan Setyawan. 2000. Komposisi tanah yang telah lama disewakan di daerah
Tugumulyo Sumatra Selatan. Journal Tanah Tropika VIII :131-138.