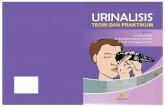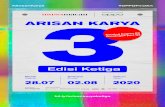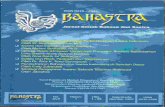Apresiasi Lemari Rebana Karya Pipin Idris (tekstual dan kontekstual)
Calon Arang Karya Pramoedya Ananta Toer dan Janda dari Jirah Karya Cok Sawitri : Kajian...
Transcript of Calon Arang Karya Pramoedya Ananta Toer dan Janda dari Jirah Karya Cok Sawitri : Kajian...
1
CERITA CALON ARANG KARYA PRAMOEDYA ANANTA TOER DAN JANDA
DARI JIRAH KARYA COK SAWITRI :
KAJIAN INTERTEKSTUAL DAN POSTKOLONIAL
Oleh :
Laga Adhi Dharma
Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Sastra FIB UGM
Email: [email protected]
Abstrak
Tulisan ini akan mencoba menelaah bagaimana relasi kekuasaan Jawa dan Luar Jawa
yang terdapat dalam Cerita Calon Arang Karya Pramoedya Ananta Toer dan Janda dari
Jirah Karya Cok Sawitri. Melalui konsep Jawa sebagai pusat (superior) dan “yang lain”
adalah pinggirannya (inferior), mengakibatkan munculnya persepsi dari beberapa wilayah
bahwa Jawa dicitrakan sebagai ”bangsa” yang layak diwaspadai dan dipinggirkan karena
kekuasaan Jawa menjadi sangat dominan. Jawa menjadi ancaman potensial yang harus
dilawan meskipun hanya pada tataran wacana.
Teori yang digunakan dalam tulisan ini mengunakan teori intertekstual untuk
melakukan perbandingan Calon Arang berdasarkan teks hipogram dan transformasinya, serta
melihat dengan kacamata postkolonial untuk menguraikan hasil interteks yang telah
dilakukan. Dari analisis yang dilakukan terjadi tiga proses inferiorisasi, yaitu : politik, sosial
keagamaan dan gender. Proses tersebut melahirkan resistensi, baik bersifat radikal atau
mimikri.
Kata Kunci: Calon Arang, Jawa sebagai pusat, inferiorisasi, resistensi
A. Pendahuluan
Jawa adalah pusat. Konsep inilah yang selalu dinarasikan teks lama, terutama yang
berasal dari kerajaan Jawa. Muncul konsep otherism atau otherness, di luar Jawa. Dasar
pandangan itu bersifat etnosentris yang memandang bahwa diri sendiri, etnis atau bangsa
sendiri (dalam konteks ini Jawa) adalah makhluk terpilih atau lebih mulia dibanding yang
2
lain. Konsep ini lebih lanjut memunculkan superioritas etnis atau bangsa tertentu.
Superioritas adalah konsep politik dan sosioekonomi yang berkaitan dengan peristiwa-
peristiwa politik, militer, sejarah ekonomi yang mutakhir serta tradisi kultural dari suatu
negara atau kelompok (Harrison, 2003: 74). Padahal, superioritas ras adalah sebuah konstruk
sosial (Brace, 2006: 270). Dia dipersepsikan, agar memperoleh kemenangan dalam kontestasi
wacana yang berkembang saat itu.
Dengan demikian, “perbedaan” pada dasarnya adalah persoalan psikologis. Orang
cenderung curiga terhadap siapa saja yang kelihatan berbeda. Dari sinilah, persepsi terhadap
“yang beda” pada hakikatnya berpusat pada diri. Lebih lanjut, Brace mengatakan bahwa
Liyan adalah diri dan semua realitas adalah subjektif karena merupakan konstruk (Brace,
2006). Hal inilah yang menarik untuk dikaji, ketika melihat Jawa sebagai pusat dan “yang
lain” adalah pinggirannya. Kondisi ini mengakibatkan, munculnya persepsi dari beberapa
wilayah bahwa Jawa dicitrakan sebagai ”bangsa” yang layak diwaspadai dan dipinggirkan
karena kekuasaan Jawa telah menjadi sangat dominan. Jawa menjadi ancaman potensial yang
harus dilawan dan diberontaki meskipun hanya pada tataran wacana. Narasi seperti Hang
Tuah (Melayu), Trunojoyo (Madura), hingga Calon Arang (Bali) adalah beberapa contohnya.
Calon Arang adalah salah satu cerita yang menarik untuk dikaji. Teks pertama tentang
Calon Arang diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda oleh Poerbatjaraka (1926), yaitu LOr
5279 (5387), LOr 4562 dan LOr 4561. Terjemahan bebas dari salah satu versi Calon Arang
dimuat dalam majalah Bahasa dan Budaya No. 2/1954. Tardjan Hadidjaja menerbitkan
ringkasan cerita Calon Arang dalam Kepustakaan Jawa (1957). Pekerjaan ini dilanjutkan
oleh Soewito Santoso yang menerjemahkan Calon Arang dari bahasa Belanda (yang disusun
Poerbatjaraka) ke dalam bahasa Indonesia berjudul Calon Arang, Si Janda dari Girah (1975).
Teks ini juga diminati oleh C. Hooykaas, yang menyajikan episode cerita Calon Arang dalam
bahasa Belanda (1933) dan menerbitkannya lagi pada tahun 1979. Sementara J. Gonda (1933)
membuat catatan kata-kata Jawa Kuna yang diberi arti yang diambil dari De Calon Arang
edisi Poerbatjaraka (Suastika, 1997:6–7). Semua teks ini memosisikan Calon Arang sebagai
subjek yang “salah” dan perlu untuk ditumpas.
Dalam perkembangannya, muncul teks transformasi yang menjadikan teks Calon
Arang tersebut sebagai hipogram, diantaranya : Pramoedya Ananta Toer dalam Cerita Calon
Arang (2003) yang pernah terbit sebelumnya dengan judul Dongeng Calon Arang (1954).
Femmy Syaharani dalam Galau Putri Calon Arang (Gramedia, 2005) dan Toety Heraty
menulis kajian feminisme berdasarkan legenda Calon Arang berjudul Calon Arang: Kisah
3
Perempuan Korban Patriarki (YOI, 2000). Selain itu, ada pula Cok Sawitri yang terinspirasi
dari cerita ini yang menulis novel Janda dari Jirah.
Dari berbagai teks transformasi, minimal ada dua narasi besar yang bisa menjadi
poros utama, yaitu mengikuti pola yang ada (sebagaian besarnya) dan melakukan dekontruksi
(inovasi). Teks adalah sebuah metafora yang melihat keseluruhan kompleks wacana sebagai
suatu anyaman atau tenunan (Segers, 1988:300). Dengan demikian, apabila sebuah teks
dibaca, baik oleh pembaca individual maupun oleh suatu kelompok dengan cara
berkomunikasi dengannya, teks di tenun atau dianyam kembali berdasarkan benang-benang
lain yang jumlahnya tidak terbatas (Barthes via Young, 1981:32).
Cerita Calon Arang karya Pramoedya Ananta Toer adalah salah teks yang tidak
banyak melakukan dekontruksi (inovasi), sehingga relatif mengikuti pola hipogramnya.
Tokoh-tokohnya digambarkan memiliki karakter yang hitam-putih. Raja Airlangga dan Empu
Baradah digambarkan sebagi protagonis perlambang kebajikan dan Calon Arang
digambarkan sebagai antagonis perlambang kejahatan yang harus dibinasakan. Mungkin
karena prioritas menjadikan karyanya ini sebagai karya sastra anak (bervisi pembelajaran)
menjadikan ruang inovasi relatif minim (Toer, 1999:v-vi). Mungkin juga, pengaruh
feodalisme Jawa yang masih kentara di benak Pramoedya, sehingga proses narasi besarnya
masih memosisikan Jawa sebagai pusat. Kondisi ini berbeda dengan karya Janda dari Jirah
karya Cok Sawitri. Dia justru membongkar relasi kekuasaan Jawa melalui novel tersebut.
Calon Arang tentu dipersepsikan berbeda dengan apa yang diwacanakan sebelumnya.
Untuk itu, kajian terhadap keduanya adalah pilihan yang menarik. Komparasi
terhadap wacana yang muncul terhadap keduanya diharapkan memunculkan cara pandang
kita terhadap wacana kekuasaan tertentu, yaitu pengukuhan kekuasaan terhadap Jawa dan
proses resistensinya.
B. Perbandingan Terjemahan Teks Calon Arang Prosa LOr 5387/5279 dengan Cerita
Calon Arang Karya Pramoedya Ananta Toer dan Janda dari Jirah Karya Cok Sawitri
Terjemahan Teks Calon Arang Prosa LOr 3587/5278 yang dilakukan oleh I Made
Suastika dipilih sebagai hipogram dalam analisis ini. Mengacu pada apa yang diungkap
Riffaterre, teks hipogram adalah teks yang melatarbelakangi penciptaan teks-teks yang lahir
kemudian (1984:23). Hipogram dapat tercipta diantaranya melalui klise-klise dan kutipan
dari teks-teks lain (Riffaterre, 1984:63). Tulisan terjemahan ini didasarkan pada tulisan I
Made Suastika (1997:92–127), sebagai bagian dari hipogram.
4
Dimulai dengan menceritakan seorang pendeta bernama Mpru Baradah yang tinggal
di Lemah Tulis. Dikemudian hari, diketahui bahwa istri dari Mpu Baradah sakit lalu
meninggal dunia. Mpu Baradah akhirnya hidup dengan anaknya yang bernama Wedawati.
Namun dalam perjalanannya, Mpu Baradah memutuskan untuk menikah lagi meskipun
mendapat tentangan oleh anaknya. Pernikahan berlangsung dan akhirnya Wedawati memiliki
ibu tiri yang tidak begitu suka kepadanya. Akhirnya Wedawati berusaha untuk melarikan diri
sari rumah dan mendatangi makam ibu kandungnya. Hal ini diketahui oleh Mpu Baradah
yang akhirnya membuatkan asrama di kuburun mantan istrinya tersebut, tempat yang tadinya
dianggap angker lalu dirubah menjadi tempat yang indah yang akhirnya ditempati oleh
Wedawati.
Diceritakanlah seorang raja yang sangat termashyur memimpin kerajaan Daha
bergelar Maharaja Airlangga, mulai gelisah karena ada janda di wilayahnya yang memiliki
ilmu hebat dan jahat bernama Calon Arang bertempat tinggal di Girah dan memiliki seorang
anak bernama Ratna Manggali. Calon Arang mendapatkan perhatian khusus karena
kekuatannya dapat mengacam kekuasaan Maharaja Airlangga dalam menjalankan roda
pemerintahan di Kerajaan Daha. Untuk mengantisipasi kekuatan jahat Calon Arang supaya
tidak meluas akhirnya Maharaja Airlangga mengutus Ken Kanuruhan untuk menemui Mpu
Baradah agar meruwat kerajaannya, supaya terbebas dari segala bentuk kejahatan terutama
yang dilakukan oleh Calon Arang.
Ahirnya setelah menemui Mpu Baradah, Kanuruhan disuruh pulang dan Mpu
Baradah mengutus Mpu Bahula untuk mengikutinya dengan tujuan untuk menikahi putri
Calon Arang yaitu Ratna Manggali. Dengan cara tersebutlah perlahan kekuatan Calon Arang
mudah dibaca oleh Mpu Baradah. Setelah sampai Girah, Mpu Bahula langsung menemui
Calon Arang dengan mengutarakan maksudnya untuk menikahi Ratna Manggali. Keinginan
tersebut langsung diamini oleh Calon Arang karena sejatinya Ratna Manggali memang
sedang mencari jodoh. Setelah menjadi keluarga, akhirnya Mpu Bahula dan Ratna Manggali
tinggal di Girah. Lama kelamaan, aktifitas Calon Arang terpantau jelas oleh Mpu Bahula,
sehingga kekuatan Calon Arang dapat diketahui oleh Mpu Bahula karena menurut
informasinya dari Ratna Manggali Calon Arang mempunyai lipyakara, yang berisihan
tentang ajaran menuju kesempurnaan, tetapi oleh Calon Arang ajaran di dalam lipyakara
tersebut dibelokkan, sehingga yang dijalankan oleh Calon Arang adalah ilmu sihir yang
dapat menyesatkannya di dunia.
Setelah lipyakara tersebut berhasil diserahkan oleh Mpu Baradah, akhirnya Mpu
Baradah berusaha datang ke Girah dan mencoba untuk menaklukkan Calon Arang. Dengan
5
menggunakan astacapala Calon Arang akhirnya dapat ditaklukkan oleh Mpu Baradah.
Maharaja Airlangga merasa sangat bahagia mendengar Calon Arang telah ditaklukkan oleh
Mpu Baradah, sehingga segala jenis bentuk balas jasa diberikan oleh Maharaja Airlangga
kepada Mpu Baradah.
Setelah Kerajaan Daha mengalami kemakmuran, muncul lagi perpecahan dalam
keuarga kerajaan sehingga Maharaja Airlangga membagi kerajaannya menjadi dua bagian
yaitu Jenggala dan Kadiri. Kerajaan Jelangga kelak akan dipimpin oleh anak turun dari Ken
Apatih anak Maharaja Airlangga yang pertama, sementara Kerajaan Kadiri dipimpin oleh
Ken Kanuruhan anak yang nomor dua. Meskipun dalam perjalanannya kedua kerajaan ini
juga saling bersitegang, tetapi hal tersebut dapat diredam oleh Mpu Baradah yang akhirnya
kedua kerajaan tersebut memiliki hubungan yang harmonis. Di akhir cerita, Mpu Baradah
dapat moksa dengan anaknya Wedawati dengan tenang.
Kemudian, bagaimana perbandingan yang muncul ketika dihadapkan pada teks
transformasinya, karena setiap teks adalah mozaik kutipan-kutipan, penyerapan dan
transformasi dari teks lain (Kristeva via Culler, 1975:139). Artinya, sebuah karya sastra pada
dasarnya merupakan tanggapan terhadap teks sebelumnya (Teeuw, 1983:19). Eksplorasi lebih
lanjut, akan dijelaskan sebagai berikut.
B.1 Calon Arang
Dalam terjemahan teks ini Teks Calon Arang Prosa LOr 3587/5278 Calon Arang
digambarkan sebagai sosok yang sesat karena memiki sihir jahat.Sebenarnya pustaka yang
dimiliki Calon Arang yaitu lipyakara merupakan kitab ajaran untuk menuntun manusia
sehingga memperoleh kesempurnaan hidup di dunia. Namun, hal tersebut oleh Calon Arang
sengaja diputar balikkan ajarannya, sehingga yang dijalani oleh Calon Arang merupakan hal
sesat yang dapat menimbulkan kekacauan terhadap masyarakat sekitar terutama masyakarat
Girah dan lebih luas adalah masyarakat Kerajaan Daha. Sosok yang jahat terus melekat pada
diri Calon Arang sehingga Raja Airlangga memutuskan untuk melenyapkan keberadaan
Calon Arang di wilayah kerajaannya, sebelum dia justru semakin menyengsarakan warga
kerajaan Daha.
8a: “Sang Raja berkata dengan sedih. Kemudian beliau marah.“Manakah rakyat dan
parjuritku” tidak lama bersamaan datang prajurit “tentara rahasia”. “pergilah kamu,
serbu dan bunuh Calon Arang. Jangan engkau seorang diri, hendaklah engkau
membawa prajurit yang banyak, jangan lengah” (Suastika, 1997: 97).
6
Konsep ini relatif sama, dengan apa yang ditulis Pramoedya. Calon Arang dalam
penggambaran Pramoedya merupakan lambang sisi gelap manusia dengan segala sifat
buruknya. Dalam karya Pramoedya, Calon Arang sebagai perempuan pembawa bencana
bagi Kerajaan Daha (sekarang Kediri) karena berambisi menjadi penguasa dengan
tindakannya yang tidak manusiawi, yaitu membunuh, merempas, dan menyakiti.
Calon Arang seorang perempuan setengah tua. Ia mempunyai seorang anak perawan
yang berumur lebih dua puluh lima tahun. Ratna Manggali namanya. Bukan main
cantik gadis itu.
Sekalipun demikian tak seorang pun pemuda yang datang meminang, karena takut
kepada ibunya, Calon Arang. Calon Arang ini memang buruk kelakuannya. Ia senang
menganiaya sesama manusia, membunuh, merampas dan menyakiti. Calon Arang
berkuasa. Ia tukang teluh dan punya banyak ilmu ajaib untuk membunuh orang.
Sebagai pendeta perempuan pada Candi Dewi Durga banyak sekali murid dan
pengikutnya. Ia seorang dukun yang banyak mantranya. Dan mantra-mantranya itu
manjur belaka. Itulah sebabnya tak ada orang berani padanya (Toer, 1999: 3-4).
Berbeda dengan sosok Calon Arang yang digambarkan dalam karya Cok Sawitri
berjudul Janda dari Jirah. Dalam novel Sawitri ini, Calon Arang dipanggil Rangda Ing Jirah
atau Ibu Ratna Manggali. Rangda adalah pendeta perempuan yang taat menjalankan ajaran
Budha. Sosok perempuan baik tampak dalam diri Calon Arang yaitu lembut, berwibawa,
dan tegas dengan bukti wilayah Kabikuan Jirah yang dipimpinnya hidup damai dengan
limpahan hasil sawah, ladang, dan ternak. Hal ini adalah gambaran sosok yang sangat
kontras dengan Calon Arang dalam hiprogram yang telah saya jelaskan di atas. Calon Arang
dalam hipogramnya digambarkan sebagai penganut siwa akan tetapi dalam Cok Sawitri
Calon Arang merupakan penganut Budha. Bukti atas semuanya itu, dapat dianalisis dari teks
berikut.
“Hamba pun demikian, Bapa. Dalam perlindungan Hyang Budha, hamba dikirim ke
Jirah untuk belajar hidup. Seperti yang Bapa ketahui, selama masa belajar, hamba
tidak diperkenalkan untuk keluar Kabikuan oleh ibu...(Sawitri, 2007:156).
“Jika dibandingkan dengan Kabupaten Galuh, sesungguhnya luas Jirah lebih luas dan
dari kemakmuran mereka lebih makmur...”
Airlangga mengerutkan keningnya. Kabikuan Jirah dekat dengan Wura Wuri, apalagi
ratu Wura Wuri penganut Tantrayana, pastilah sangat menghormati pemimpin
Kabikuan Jirah. Berdebarlah hatinya memberi tanda dalam ingatannya, tak satu pun
pendeta dari Kabikuan Jirah pernah menghadap ke istana untuk memohon derma.
Sepetak tanah apalagi, sejumput rumput mereka tak pernah meminta (Sawitri, 2007:
32).
7
B.2 Raja Airlangga
Raja Airlangga digambarkan sebagai sosok raja yang peduli terhadap rakyatnya.
Kerajaan Daha yang digambarkan dalam kesejahteraan dan termashyur, sebelum
kemunculan ilmu hitam Calon Arang. Hal ini dapat dianalisis dari teks berikut. Teks yang
menceritakan kemasyuran kerajaan.
Tidak lama datanglah jamuan dengan segala perlengkapan upacara sangat indah
kelihatannya, tuak, nasi, ikan, tampo, berem, kilang, juga serebad badur (Suastika,
2007:102)
Kondisi ini sama dengan teks Pramoedya yang memosisikan Raja Airlangga sebagai raja
yang agung, berwibawa, bijaksana dan berbudi. Hal ini dapat dianalisis dari teks berikut.
Yang memerintah negara itu Airlangga namanya. Baginda terkenal bijaksana dan
berbudi. Pendeta-pendeta yang membuka pertapaan dan asrama sampai jauh di gunung-
gunung mendapat perlindungan belaka (Toer, 1999: 2).
Kondisi ini berbeda dengan apa yang diungkap dalam teks Janda dari Jirah. Kegelisahan,
selalu menyelimuti kehidupan kerajaan, karena konflik internal.
Dengan muram, Airlangga menyampaikan “keponakanku, Samarawijaya telah tiba,
bukan soal dia di mana selama ini. Semua pusaka Medang ia yang membawa aku
meminta kalian memberiku nasihat, sebab aku tidak mau ketenangan Kediri terusik
oleh pertikaian antar saudara...” (Sawitri, 2007:157).
Selain itu, dalam karya Cok Sawitri, dua tokoh anak Raja Airlangga Ken Apatih dan Ken
Kanuruhan tidak disebutkan.
B.3 Mpu Baradah dan Mpu Bahula
Mpu Baradah sangat berperan dalam cerita Calon Arang versi hipogram, disini Mpu
Baradah menjadi tokoh sentral yang dapat menjembatani keinginan Raja Airlangga dan
keturunan-keturunannya. Peran Mpu Baradah sangat keliatan pada saat diminta oleh Raja
Airlangga untuk menaklukkan Calon Arang. Mpu Baradah pula yang mengusulkan taktik
agar dilakukan penaklukan secara persuasif, hal tersebut yang akhirnya diperankan oleh
Mpu Bahula muridnya yang menikahi Ratna Manggali anak dari Calon Arang. Strategi ini
cukup berhasil sebagai langkah awal untuk penaklukan Calon Arang, karena setelah Mpu
Bahula menikah dengan Ratna Manggali terbeberkan dari mana kekuatan Calon Arang.
8
Melalui Mpu Bahula, akhirnya Mpu Baradah mempelajari kitab lipyakara yang dijadikan
pedoman Calon Arang menjalankan ilmu hitamnya. Meskipun menurut Mpu Baradah
lipyakara berisi tentang ajaran-ajaran kesempurnaan hidup, tetapi justru diputar balikkan
oleh Calon Arang mengenai isinya tersebut.
18a :Ketika Calon Arang sedang pergi ke kuburan. Pustaka (lipayakara) itu diberikan
oleh sang Manggali kepada kakaknya. Lalu dibaca oleh Mpu Bahula, kemudian
hendak minta ijin kepada adiknya untuk dimohonkan nasihat kepada Sang Pendeta.
Lalu diijinkannya. Mpu Bahula segera pergi menuju Buh Citra. Tidak diceritakan
dalam perjalanan. Ia Segera datang di asrama (Suastika, 1997: 104).
Kondisi ini sama dengan teks Cerita Calon Arang karya Pramoedya Ananta Tour.
Proses dan pesitiwa pun hampir sama. Hanya saja, ada perbedaan situasi Calon Arang,
ketika diambil kitabnya. Jika teks hipogramnya ada di kuburan. Dalam teks Pramoedya ini,
situasi calon Arang sedang tertidur.
Pada suatu hari Calon Arang sedang tidur. Nyeyak sekali tidurnya. Bersitinjak Ratna
Manggali mendekati tempat tidur. Dengan tak terdengar oleh ibunya, kitab bertuah
itu di ambilnya. Segera diserahkannya kitab itu kepada suaminya (Toer, 1999:79).
Dalam karya Cok Sawitri, Mpu Baradah adalah perantara hubungan antara Airlangga
dengan Rangda. Disini Mpu Bahula yang menikah dengan Ratna Manggali merupakan
proses yang terjadi secara alami karena saling cinta bukan melalui perjodohan dan tidak ada
motif penaklukan Rangda seperti dalam kisah hipogramnya, tetapi ada motif agama. Mpu
Bahula membantu ibu mertuanya menjalankan tatakrama di Kabikuan dan juga menjadi
bagian dari Kerajaan Daha. Hal ini dapat dianalisis dari teks berikut.
“Ada masa di mana ajaran Budha akan memenuhi semua pilah daun lontar, ada masa
di mana kalian akan diburur-buru. Jangan menangis pabila seorang lelaki bernama
Bahula tiba. Dia sesungguhnya mencintaiku, dan sesungguhnyalah ajaran Ibu akan
dilanjutkan oleh keturunan kami. Namun dia seorang sisia yang taat” (Sawitri, 2007:
37).
B.4 Ratna Manggali
Ratna Manggali pada teks terjemahannya merupakan tokoh penting dalam
penaklukan Calon Arang, meskipun Ratna Manggali merupakan anak kandung dari Calon
Arang sendiri. Ratna Manggali dikisahkan memang tidak mengetahui apabila pernikahannya
dengan Mpu Bahula merupakan strategi Raja Airlangga untuk menaklukan Calon Arang.
9
Disini peran Mpu Bahula sebagai eksekutor yang diperintahkan langsung oleh Mpu Baradah
sangat berhasil membuat dia diterima oleh Calon Arang dan Ratna Manggali sendiri,
sehingga kepercayaan penuh yang diberikan kepada Mpu Bahula. Peristiwa penting yang
dilakukan oleh Ratna Manggali adalah pada saat Mpu Bahula menanyakan perihal Calon
Arang yang setiap malam melakukan ritual di kuburan. Pada saat itu Ratna Manggali
memberikan pustaka (lipyakara) yang digunakan Calon Arang sebagai acuan dalam
melakukan ritual-ritualnya di kuburan. Berikut rayuan Mpu Bahula kepada istrinya yang
akhirnya, berhasil mempengaruhi Ratna Manggali, sehingga diceritakan semuanya tentang
apa yang dilakukan oleh Calon Arang.
17b: “Dinda, adikku tercinta, mengapakah ibu selalu pergi pada malam hari? Saya
khawatir Dinda, dengan ibu. Beritahulah sesungguhnya, Adikku! Apakah sebenarnya
pekerjaan ibu”(Suastika, 1997: 104).
Konteks ini sama dengan apa yang ditulis oleh Pramoedya dalam Cerita Calon Arang. Hal
ini dapat dianalisis dari teks berikut.
“kemanakah setiap sore ibu pergi sendirian?
Kelihatannya perlu sekali.
........
“Tidakkah engkau menghawatirkan ibu?” Tanya Bahula
“Tidak”, jawab Ratna Manggali (Toer, 1999:77).
Dalam Janda dari Jirah, disebutkan juga bahwa Ratna Manggali mengetahui jodohnya
sebelum Bahula datang. Hal itu karena kekuatan dalam melihat masa depan yang dimilikinya.
Siapa pun yang tinggal dan hidup di Kabikuan akan memiliki kekuatan di luar nalar manusia.
Jadi situasi dalam teks hipogram atau teks Pramoedya tidak ada. Hal ini dapat dianalisis dari
teks berikut.
“Kelak di sebuah pulau kecil, dari mana lelaki yang melompati air berasal, akan lahir
tradisi yang mentaati ajaran Ibu... ” Ratna Manggali memulai kisahnya, “dengarlah
penganut Budha kecil, tujuh turunan dari sekarang, keturunanmu akan menyeberang ke
sana. Kalian harus sabar mengikuti kemauan zaman. Ada masa di mana ajaran Budha
akan memenuhi semua pilah daun lontar, ada masa di mana klaian akan diburu-buru.
Jangan menangis pabila seorang lelaki bernama Bahula tiba. Dia sesungguhnya
mencintaiku, dan sesungguhnyalah ajaran Ibu akan dilanjutkan oleh keturunan kami.
Namun dia seorang sisia yang taat. Mengalahkan segala kebenaran dan mengalahkan
segala cinta. Dia bagai Ganesha, murid siwa yang utama. Dia bagaikan Iswaku di mata
Patanjali...” (Sawitri, 2007: 36).
10
B.5 Wedawati
Wedawati merupakan tokoh yang pada awal pembukaan teks terjemahan Calon
Arang menjadi tokoh sentral. Wedawati merupak anak dari Mpu Baradah dari istri yang
pertama. Wedawati diceritakan tidak setuju apabila Mpu Baradah menikah lagi, sehingga
ketika Mpu Baradah menikah dia lebih memilih sering tinggal di kuburan ibu nya yang telah
meninggal. Sampai pada akhirnya Wedawati dibuatkan asrama di kuburan tersebut, sehingga
dia tetap dapat tinggal berdampingan dengan ibunya. Di akhir cerita Wedawatilah yang
menganjurkan Mpu Baradah moksa bersama dengannya karena urusan duniawi telah
terselesaikan.
50b: Setelah beliau selesai berkata, segera moksa Sang Maha Bijaksana berdua
bersama putrinya. Sang Wedawati, moksa hilang lenyaplah dia. (Suastika, 1997: 127).
Konsep itu, juga mengalami persamaan dengan teks Pramoedya. Widyawati ditinggalkan
ibunya. Kemudian, dia memilih nertempat tinggal di kuburan, karena mengalami percecokan
dengan sang ibu. Akhirnya, keduanya pergi (meskipun tidak disebutkan moksa).
Maka nampaklah kedua kedua orang itu berjalan bersama-sama, naik gunung.
Tambah lama, tambah kecil penglihatannya (Toer, 1999:101).
Sedangkan dalam Cok Sawitri, tokoh Wedawati ini justru tidak disebutkan sama sekali,
sehingga tidak cerita tentang Wedawati.
B.6 Keterpecahan Kerajaan Daha
Ada dua versi, bagaimana proses keterpecahan kerajaan Daha. Dalam Pramoedya,
proses keterpecahan itu muncul dari inisistif Airlangga dan diberikan kepada kedua anaknya.
Konsep ini berbeda dengan apa yang diungkap Sawitri. Dalam Janda dari Jirah, proses
keterpecahan itu justru hadir karena tanah di Jirah telah diberikan kepada Samarawijaya
(keponakannya). Merespon itu, agar tidak terjadi polemik, barulah Airlangga membagi
kerajaannya menjadi dua, untuk keponakannya dan anaknya. Hal ini bisa dibandingkan dari
kutipan dari kedua novel berikut.
“Tuanku, baiklah kerajaan ini diparoh dua. Yang sebelah dinamaiKediri dan
diperintah oleh putra sulung. Yang sebelah lagi dinamai Jenggala dan diperintah oleh
putra bungsu” (Toer, 1999:100).
11
“Mereka juga membeli tanah-tanah di desa-desa lain dan setiap tahun mereka
membuka sawah dan ladang yang baru...”
Tanpa senjata mereka meluaskan wilayah. Airlangga tersenyum lagi karena
terkagum-kagum. Banyak hal yang harus ia pelajari sebagai penguasa baru.
Setiap bulan para telik sandi mengirimkan laporan tentang desa-desa yang
letaknya dekat dengan Wura-Wuri, namun hanya Kabikuan Jirah yang selalu
menjadi perhatian Airlangga (Sawitri, 2007:32).
Bagian yang semula dikenal sebagai ibukota Medangakan diserahkan kepada
Samarawijaya, anakku dari sepupu, sebagian yang lain yang dikenal dengan
Daha, akan ku serahkan pada sepupu Samara Wijaya, putriku, putri mahkota ing
Daha (Sawitri, 2007:181)
C. Cerita Calon Arang dan Janda Dari Jirah : Kajian Postkolonial
Cerita Calon Arang dapat dilihat menggunakan kacamata postkolonial. Secara tersirat
maupun tersurat, cerita Calon Arang mengkonstruksikan kelompok dominan dan kelompok
inferior. Said menjelaskan istilah timur dan barat. Timur ditujukan untuk kelompok inferior
dan barat sebagai kelompok dominan. Pada cerita Calon Arang, kelompok dominan adalah
manusia Jawa yang direpresentasikan oleh Airlangga. Sedangkan kelompok yang
diinferiorkan adalah manusia di luar Jawa (Bali) yang direpresentasikan oleh Calon Arang.
Menurut Edward Said, orang Eropa (Barat) menganggap Timur sebagai tempat yang
penuh romansa, makhluk-makhluk eksotik, dunia yang asing, misterius, primitif, brutal
kenangan, panorama yang indah, dan pengalaman-pengalaman yang mengesankan (2010:1).
Hal ini sesuai dengan penggambaran Calon Arang. Calon Arang versi Pramoedya
digambarkan sebagai seorang janda yang tinggal di dusun Girah. Dalam versi ini, Calon
Arang beserta daerah tempat tinggal dan para pengikutnya dianggap sebagai tempat yang
misterius, penuh dengan keburukan. Oleh sebab itu raja Airlangga sebagai representasi
kelompok dominan menginginkan dusun Girah untuk dikuasai.
Hal ini juga ditemukan dalam cerita Calon Arang versi Cok Sawitri (2007). Calon
Arang dalam novel disebut Ibu Ratna Manggali menduduki suatu tempat yang dijuluki
Kabikuan. Tempat ini dianggap sebagai tempat yang berbeda dengan tempat yang lain.
Bahkan terdapat teks yang menguatkan hal ini.
“...para pedagang di pasar bahkan semua penduduk Kadiri tahu, bagaimana perilaku
murid-murid Kabikuan Jirah, “mereka tak jelas jenis kelaminnya...hehe!” ucap para
lelaki yang kebingungan setiap memperhatikan orang-orang Kabikuan.” (Sawitri,
2007: 28).
12
Dalam konteks ini, Kabikuan Jirah dianggap inferior, meskipun pada versi ini Airlangga
mengakui kebesaran Calon Arang.
Pada versi Pramoedya, dusun Girah terasa jauh dengan dusun lain karena orang sangat
takut mendekati dusun ini. oleh sebab itu dusun ini dikucilkan oleh warga yang lain.
Sedangkan pada versi Sawitri, Kabikuan Jirah digambarkan tempat suci pemberian raja-raja
terdahulu kepada para pendeta yang tidak boleh dilalui oleh para pegawai kerajaan. Tempat
bermukimnya Calon Arang beserta murid-muridnya “terasa” sulit dijangkau tersebut adalah
sebuah tempat yang sebenarnya bersebelahan dengan permukiman warga, bahkan adalah
bagian dari kerajaan Kediri itu sendiri. Namun, karena ia adalah kawasan yang “dianggap”
melahirkan beragam misteri, ia menjadi liyan. Batas abstrak tersebut kemudian menjadi garis
imajinatif yang membedakan antara “kita” dan “mereka”.
Hal ini bisa disamakan dengan Timur dalam wacana orientalisme. Bagi orang-orang
Eropa, Timur tidak hanya bersebelahan dengan kawasan mereka… (tetapi juga) bagian dari
imajinasi Eropa yang terdalam. Timur adalah “yang lain” (the other) bagi Eropa (Said,
1994:2). Dengan demikian, Timur yang antah berantah adalah imajinasi Barat belaka. Dalam
pembahan ini, akan dipaparkan bagaimana inferioritas ini dimunculkan oleh kelompok
dominan. Akibat adanya pembedaan kelompok ini akan memunculkan resistensi bagi
kelompok yang terinferiorkan. Oleh sebab itu, pada analisis ini juga disertakan resistensi-
resistensi yang muncul.
C.1 Inferiorisasi Politik dan Resistensinya
Secara politik, baik dusun Girah atau Kabikun Jirah termasuk dalam kekuasaan Kadiri
(Daha), sehingga wilayah tersebut harus tunduk terhadap aturan dari kerajaan. Cerita Calon
Arang versi Pramoedya, Calon Arang diinferiorkan oleh Airlangga dengan berbagai cara,
antara lain menyebarkan isu bahwa Calon Arang dan murid-muridnya menganut ajaran sesat,
dianggap berbahaya, siapa yang berani melawan akan dimusnahkan, suka membunuh, jahat,
atau berkeramas menggunakan darah manusia. Apa yang dilakukan Calon Arang tersebut
dianggap mengganggu stabilisasi keamanan kerajaan. Oleh sebab itu, Airlangga juga
melakukan perlawanan guna melindungi daeraah kekuasaannya.
“Penyakit ini harus dilenyapkan. Kalau tidak bisa, setidak-tidaknya harus dibatasi.
Kirimkan balatentara ke dusun Girah. Tangkap Calon Arang. Kalau melawan, bunuh
dia bersama murid-muridnya.”(Toer, 2010: 32).
13
Resistensi yang dilakukan Calon Arang adalah dengan menghukum (menenung)
orang-orang yang menyakiti kerabat-kerabatnya. Bahkan beberapa kali dicceritakan prajurit
Airlangga dilawannya dengan mudah. Selain itu, Calon Arang juga melakukan resistensi
dengan menyembah dewi Durga. Dengan menyembah dewi Durga tersebut, Calon Arang
berusaha memperluas guna-guna sampai mendekati kawasan dalam keraton.
Penyakit tambah menghebat. Ratusan orang mati tiap hari. Tak sempat lagi orang
menguburkan kerabat atau sahabat yang meninggal. Mayat tergolek di sepanjang jalan,
di dalam rumah, di sawah, bahkan di dekat-dekat istana demikian pula (Sawitri,
2007:53).
Namun apa yang dilakukannya memunculkan ambivalensi. Di satu sisi ia ingin
membunuh semua orang yang ada di sekitarnya, di sisi lain ia masih berharap ada laki-laki
yang mau menikahi putrinya. Konsep Bhaba, yaitu menyebut bahwa proses meniru, bisa
menjadi proses resistensi pribumi. Baginya, proses peniruan tidak pernah lengkap atau
sempurna. Begitupun dengan hasilnya, bukan sebuah gambaran yang sempurna karena
otoritas kolonial dibuat “ambivalen”, sehingga membuka ruang bagi terjajah untuk
menyelewengkan wacana induk (Bhabba via Loomba, 2003:117).
Cerita Calon Arang versi Cok Sawitri (2007) menggambarkan sosok Calon Arang
yang memiliki kekuasaan yang lebih. Wilayah kekuasaannya bisa dikatakan makmur. Hal ini
dapat dianalisis dari teks berikut.
Banyak yang percaya, air di Kabikuan Jirah memangberbeda, karena disucikan setiap
purnama, mereka sangat taat memuja Brahma dan menjalankan agama Budha, karena
itu tangan mereka menjadi dingin, segala yang disentuh akan bermanfaat (Sawitri,
2007:30).
Meskipun pengarang telah berupaya untuk menulisakan cerita Calon Arang dengan
sudut pandang baru (berbeda dengan cerita Calon Arang yang telah beredar), namun Calon
Arang dapat dikatakan tetap dalam posisi inferior. Calon Arang merasa terinferior setelah ia
tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Ia melihat dirinya dituduh sebagai penganut
ilmu hitam, orang yang berkhianat terhadap Airlangga, dan sebagai penyebab perang saudara
di Kediri. Di saat itu, Ratna manggali hanya menangis.
14
Anak-anak kecil itu melompat riang. Membiarkan rambut mereka lepas dan berkibas-
kibas. “Bahkan ketika kejayaan raja-raja lenyap, akan selalu pemikiran ibu yang
digunakan...” ucap merekadengan suara kanak, telah menerka apa yang diucapkan
Ratna Manggali.
...........
Ratna Manggali tak tahan tak menangis, ia jatuh dalam isak, “Oh, Ibu, ajari aku
melepas ikatan ini (Sawitri, 2007:37–38).
Pada novel ini resistensi yang dilakukan Calon Arang lebih bersifat batin. Salah satu
resistensi yang dilakukan Calon Arang adalah dengan memperluas wilayah. Ia membeli
tanah-tanah untuk dihuni dan dijadikan tempat yang subur. Bahkan tanpa sepengetahuan Raja,
Calon Arang hampir memiliki wilayah hampir seproh luas kerajaan. Selain itu diam-diam ia
memelihara cucu Dharmmawangsa Tguh, Samarawijaya. Samarawijaya merupakaan pewaris
tahta yang sah. Sehingga ia memiliki hak terhadap kerajaan Medang (Kadiri). Di akhir cerita,
Calon Arang memberikan seluruh tanahnya untuk dikuasai oleh Samarawijaya. Namun
demikian, tindakan Calon Arang tersebut merupakan sebuah tindakan ambivalensi. Di awal
cerita, Calon Arang sebagai pemimpin Kabikuan berikrar untuk tidak memihak raja manapun.
Namun pada akhirnya ia justru memberikan kekuasaan kepada Samarawijaya karena ia
adalah cucu Dharmmawangsa Tguh.
Di pihak lain, Airlangga merasa posisinya terancam. Kabikuan Jirah merupakan
kawasan suci di mana para pegawai istana dilarang untuk melawati, apalagi untuk
kepentingan perang. Banyak warga yang lebih suka tinggal di kawasan Kabikuan ini.
Alasannya adalah karena kabikuan bebas dari pajak negara, tanah subur, aman, tentra, dan
warga memperoleh banyak ilmu. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran Airlangga karena ada
kemungkinan warga lebih setia dan patuh terhadap Calon Arang daripada dia. Kedekatan
Kabikuan dengan kerajaan Wura-wuri juga menambah kekhawatiran Airlangga. Oleh sebab
itu, Airlangga mengirimkan telik sandi untuk mengawasi perkembangan Kabikuan, terutama
mengenai perluasan tanah. Hal ini dapat dianalisis dari teks berikut.
“Mereka juga membeli tanah-tanah di desa-desa lain dan setiap tahun mereka
membuka sawah dan ladang yang baru...”
....
Banyak hal yang harus ia pelajari sebagai penguasa baru. Setiap bulan para telik sandi
mengirimkan laporan tentang desa-desa yang letaknya dekat dengan Wura-Wuri,
namun hanya Kabikuan Jirah yang selalu menjadi perhatian Airlangga (Sawitri,
2007:32).
15
C.2 Inferiorisasi Sosial Keagamaan dan Resistensinya
Kedua versi cerita calon arang terdapat wacana tentang kehidupan sosial agama, yaitu
agama Budha dan Hindu Siwa. Pada versi Pramoedya diceritakan bahwa Calon Arang
menganut agama hindu yang sesat. Hal ini dikarenakan Calon Arang yang menyembah dewi
Durga guna memperkuat ilmu sihirnya. Berbagai ritual yang identik dengan ajaran sesat
adalah dengan mengorbankan nyawa orang untuk dewi durga, serta berkeramas
menggunakan darah manusia.
Raja Airlangga telah menetapkan bahwa ajaran yang disebarkan oleh Calon Arang
adalah ajaran yang sesat, mengganggu stabilisasi kehidupan sosial di Daha. Oleh sebab itu,
Calon Arang beserta ajarannya harus segera ditumpas. Calon Arang merasa tertekan. Ada
kekhawatiran pada diri Calon Arang terhadap kekuatan Airlangga. Ia kembali mengandalkan
pujaannya, yaitu dewi Durga. Hal ini merupakan resistensi yang dilakukan oleh Calon Arang,
yaitu justru dengan meneruskan perlawannanya terhadap raja Airlangga.
“Ampun, Dewi pujaan hamba. Izinkanlah hamba membuat penyakit besar-besaran.
Biarlah penyakit itu sampai merambat ke dalam ibu kota, bahkan ke dalam istana
sekalipun. Paduka Sang Dewi telah tahu juga, bahwa Sang Baginda Airlangga sangat
marah karena teluhan hamba. Sang Baginda pun telah menjatuhkan perintah untuk
membunuh hamba.”(Toer, 1999: 46).
Berbeda dengan cerita versi Cok Sawitri. Pada novel Janda dari Jirah ini sosok Calon
Arang atau lebih dikenal sebagai Rangda Jirah digambarkan sebagai penganut Budha.
Sedangkan Airlangga penganut Hindu Siwa. Terdapat suatu kekhawatiran Calon Arang akan
kehadiran Airlangga. Kekhawatiran tersebut berkaitan dengan agama Airlangga. Hal ini dapat
diamati dalam teks:
“Namun ratumu, ia sejak muda lebih menyukai ajaran Siwa, ketika masih di Jawa, ia
mencapai kesempurnaan dalam Bhairawa, kelak keturunannya akan mencapai
paripurna, ketika orang-orang berkulit kuning membuang sauh di pantai timur”
(Sawitri, 2007: 99).
Kekhawatiran Calon Arang tersebut mengindikasikan bahwa agama Budha terinferior oleh
kedatangan Airlangga yang beragama Hindu (menuju paripurna). Terdapat kemungkinan
wacana bahwa raja Airlangga akan menghindukan seluruh daerah kekuasaannya. Bahkan
tidak menutup kemungkinan akan menjalar sampai ke Bali. Orang-orang berkulit kuning
16
dalam arti representasi orang Jawa yang melempar sauh atau melakukan pelayaran.
Membuang sauh di pantai timur berarti akan menuju pulau Bali.
Berbagai tindakan yang dilakukan Calon Arang dapat diartikan sebagai wujud
resistensi dirinya mewakili agama Budha. Yang pertama adalah usaha Calon Arang yang
memperluas daerah Kabikuan, yaitu dengan membeli tanah-tanah dan mendekatkan
hubungan dengan kerajaan Wura Wuri. Hal ini dapat disinyalir sebagai usaha memperluas
kawasan ajarannya. Selain itu, secara diam-diam ia menerima Samarawijaya sebagai
muridnya. Samarawijaya dididik ajaran Budha. Dan pada akhirnya Calon Arang memberikan
seluruh wilayah Kabikuan untuk Samarawijaya. Samarawijaya merupakan keturunan
langsung dari Dharmmawangsa Tguh yang memiliki hak atas kekuasaan Kadiri. Ini
bertendensi sebagai usaha mempertahankan ajaran Budha melalui kekuasaan Samarawijaya.
Hal ini dapat dianalisis dari teks berikut.
“Hamba pun demikian, Bapa. Dalam perlindungan Hyang Budha, hamba dikirim ke
Jirah untuk belajar hidup. Seperti yang Bapa ketahui, selama masa belajar, hamba
tidak diperkenalkan untuk keluar Kabikuan oleh ibu...
“Kini pangeran telah selesai belajar. Maka tugas kami, mengantarkan ke ibu kota
untuk menghadap Rake Halu, Pananda Samara wijaya.
.........
Pusaka-pusaka kekerajaan Medang yang selama ini dicari-cariAirlanggaternyata ada
di Jirah (Sawitri, 2007:156).
C.3 Inferiorisasi Gender dan Resistensinya
Pada versi Pramoedya, puncak kemarahan Calon Arang adalah ketika tidak ada satu
laki-laki yang mau menikahi anaknya, Ratna Manggali. Tendensi yang muncul adalah baik
Calon Arang atau Ratna Manjali sebagai wanita yang terinferior, dianggap rendah derajatnya,
hina, terpinggirkan, dan sejenis manusia “tidak biasa”. Resistensi pun dilakukan, yaitu
melalui berbagai tindakan sihir yang dilakukannya, sehingga berujung kematian bagi warga
sekitar.
Penyakit tambah menghebat. Ratusan orang mati tiap hari. Tak sempat lagi orang
menguburkan kerabat atau sahabat yang meninggal. Mayat tergolek di sepanjang jalan,
di dalam rumah, di sawah, bahkan di dekat-dekat istana demikian pula (Sawitri,
2007:53).
17
Selain itu, Untuk mengatasi hal itu, Ratna Manggali haruslah menikah. Pada akhir cerita
datanglah empu Bahula yang bersedia menikahi Ratna Manggali. Empu Bahula merupakan
representasi Jawa karena empu Bahula adalah asli dari Jawa.
“bukan main girang Calon Arang. Sekarang ia tak akan disindir-sindir dan
dipercakapkan orang lagi. Sebentar lagi anaknya jadi pengantin.” (Toer, 2010: 72).
Terlihat bahwa kedatangan empu Bahula sangatlah penting. Ia tidak lagi dianggap “tidak
biasa” bagi orang lain. Dari sini dapat dikatakan bahwa Calon Arang sebagai representasi
Bali membutuhkan Bahula (manusia Jawa) agar dirinya sempurna seperti kontruksi sosial
masyarakat, yaitu wanita yang menikah.
Wacana gender yang terdapat dalam Calon Arang versi Sawitri, sebenarnya memiliki
kemiripan dengan Calon Arang versi Pramoedya. Calon Arang sama-sama membutuhkan
kehadiran sosok empu Bahula. Namun pada versi kedua ini, empu Bahula justru diharapkan
menurunkan generasi penerus ajaran Budha.
“Ada masa di mana ajaran Budha akan memenuhi semua pilah daun lontar, ada masa
di mana kalian akan diburur-buru. Jangan menangis pabila seorang lelaki bernama
Bahula tiba. Dia sesungguhnya mencintaiku, dan sesungguhnyalah ajaran Ibu akan
dilanjutkan oleh keturunan kami. Namun dia seorang sisia yang taat” (Sawitri, 2007:
37).
Sama halnya dengan versi yang pertama, Mpu Bahula dihadirkan sebagai menantu dari putri
Calon Arang untuk tujuan yang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan orang
Bali dianggap inferior daripada orang Jawa. Orang Jawa justru hadir untuk menaikan nilai
orang Bali. Munculnya ramalan masa depan, juga merupakan resistensi, ketika posisi Budha
dicitrakan semakin terdesak. Keturunan kemudian dianggap sebagai solusi untuk melanjutkan
misi keagamaan tersebut.
D. Kesimpulan
Ketika melihat Jawa sebagai pusat dan “yang lain” adalah pinggirannya. Kondisi ini
mengakibatkan, munculnya persepsi dari beberapa wilayah bahwa Jawa dicitrakan
sebagai ”bangsa” yang layak diwaspadai dan dipinggirkan karena kekuasaan Jawa telah
menjadi sangat dominan. Jawa menjadi ancaman potensial yang harus dilawan dan
diberontaki meskipun hanya pada tataran wacana. Narasi seperti Hang Tuah (Melayu),
Trunojoyo (Madura), hingga Calon Arang (Bali) adalah beberapa contohnya. Calon Arang
18
adalah salah satu cerita yang menarik untuk dikaji, karena semua teks ini memosisikan Calon
Arang sebagai subjek yang “salah” dan perlu untuk ditumpas.
Terjemahan Teks Calon Arang Prosa LOr 3587/5278 yang dilakukan oleh I Made
Suastika dipilih sebagai hipogram dalam analisis ini. Teks transformasinya mengacu pada
novel Cerita Calon Arang karya Pramoedya Ananta Toer dan Janda dari Jirah karya Cok
Sawitri. Berdasar analisis peneliti, hampir terjadi kesamaan antara teks hipogram, dengan
teks dari Pramoedya. Perbedaannya hanya pada perbedaan posisi Calon Arang ketika sedang
diambil kitabnya dan akhir cerita Wedawati. Adapun dalam teks Cok Sawitri, terjadi proses
dekontruksi tokoh sebagai representasi peristiwa, seperti; Calon Arang, Raja Airlangga,
Ratna Manggali, Mpu Barda, Mpu Bahula, hingga Wedawati.
Dalam kajian postkolonial, yang mengacu pada kedua teks transformasi tersebut,
terjadi tiga proses inferiorisasi, yaitu : politik, sosial keagamaan dan gender. Proses tersebut
melahirkan resistensi, baik bersifat radikal atau mimikri. Proses penenunan oleh Calon Arang
adalah salah satu bentuk resistensinya, sedangkan itupun memunculkan ambivalensi antara
keinginan untuk anaknya dinikahi dan banyak membunuh laki-laki karena kebenciannya.
19
Referensi
Aschroft dan Grifith dan Tiffin. 2003. Menelanjangi Kuasa Bahasa: Teori dan Praktik Sastra
Postkolonial (terj) Fatie Suwandi dan Agus Mokamat. Yogyakarta: Qalam.
Barthes, Roland. 1981. “Theory of the Text” dalam Untying The text : A Post-Structuralist
Reader. Boston: Rouledge&Kegan Paul.
Brace, C. Loring. 2006. “Race” Is aFour-Letter World: The Genesis of the Concept. New
York: Oxford University Press.
Culler, Jonathan. 1975. Structuralist Poetics: Structuralism, Linguistics and The Study of
Literature. London: Roulege & Kegen Paul.
Faruk. 2007. Belenggu Pasca-kolonial: Hegemoni dan Resistensi Sastra Indonesia.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Horrison, Nicholas. 2003. Postcolonial Criticism. Cambridge: Polity.
Junus, Umar. 1985. Resepsi Sastra: Sebuah Pengantar. Jakarta:Gramedia.
Ratna, Nyoman Kutha. 2007. Teori Metode, dan Teknik Penelitian Sastra dari
Strukturalisme hingga Postrukturalisme.: Perspektif Wacana Naratif. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Riffaterre, Michael. 1984. Semiotics of Poetry. Blomington: Indiana University Press.
Said, Edward W. 1994. Culture and Imprealism. New York: Vintage Book.
____________. 2010. Orientalisme: Menggugat Hegemoni Barat dan Mendudukan Timur
sebagai Subjek (Terj) Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sawitri, Cok. 2007. Janda dari Jirah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Segers, Rien T. 1978. The Evaluation of Literaty Texts. New York : The Peterde Rider Press.
Suastika. I Made. 1997. Calon Arang Dalam Tradisi Bali. Yogyakarta : Duta Wacana
University Press.
Toer, Ananta Toer. 2007. Cerita Calon Arang. Cetakan Ke-5. Jakarta: Lentera Dipantara.