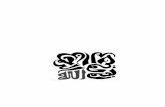Bukan Sekedar Filantropisme :Studi Kasus atas Motif dan Strategi Gerakan Muhamamdiyah dalam Menopang...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Bukan Sekedar Filantropisme :Studi Kasus atas Motif dan Strategi Gerakan Muhamamdiyah dalam Menopang...
Bukan Sekedar Filantropi?
Studi Kasus atas Motif dan Strategi Gerakan Filantropisme Muhammadiyah dalam Menopang
Keterbatasan Negara1
Oleh: Hafidz Arfandi2
Abstract:
The fall of welfare state model within economic crisis arise many critics. It was appearing idea of welfare pluralism. Welfare pluralism introduced of multi actor within social service providing consisted of state, private and volunteer sector. In the third world when welfare state hadn’t existed, volunteer sector have major role to be buffer of welfare system within limitation of state and private to reproduced welfare in society. Zakat, Infaq, Waqf and Shadaqah are part of philanthropy volunteerism which existed Islamic religious tradition. Its distribution is one potential resources to provide social service for the poorest and marginal group.
Tradition of Zakat funds distribution has been creating social service since early 20 century. Muhammadiyah born of 1912 as Islamic religious organization which it developed social service in education, health and social. Now Muhammadiyah have many thousands social service facilitates as resulted of accumulation and mobilization zakat funds from its memberships which approximately count it until 30 billion people who are spreading almost in all Indonesia region.
This research used case study of historian method to look motive and strategy of philanthropic tradition in Muhammadiyah movement. Which consisted of two philanthropy tradition, first, social service to marginal group and second, developed of social infrastructure to help limitation of state within provided it. This research focus in two question, first, what is motive of philanthropy which introduced by Muhammadiyah movement, and Second, how are relation of social and political context in institutionalization of Muhammadiyah philanthropic policy.
Key Word : Welfare Plularism, State, Philantropic, Social Service
1 Makalah ini adalah bagian dari hasil riset skripsi penulis yang berjudul: “WAJAH FILANTROPI ISLAM DI INDONESIA
:Studi Komparatif Aktivisme Sosial dan Pendayagunaan Filantropi Islam dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Sosial pada Muhammadiyah dan Dompet Dhuafa” (2014), dipresentasikan pada Workshop Internasionalisasi dan Pemikiran Muhammadiyah di UMS, Surakarta pada 31 Oktober 2014 2
Penulis adalah alumni jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, FISIPOL UGM, penulis dibesarkan dalam
keluarga Muhammadiyah dan bersama kawan-kawan di UGM sedang merintis komunitas epistemik “Diaspora Muhammadiyah Bulaksumur”
Pendahuluan
Negara memiliki keterbatasan sebagai penyedia layanan kesejahteraan bagi masyarakat. Keterbatasan
negara dalam layanan kesejahteraan sangat ditentukan oleh faktor kemampuan finansial dan
birokrasinya dalam merespon kebutuhan aktual yang dihadapi masyarakat. Ketidak mampuan negara
dalam merespon sepenuhnya tuntutan publik akan kesejahteraan melahirkan distrust terhadap
eksistensi negara yang membuka peluang pada lahirnya instabilitas dan krisis sebagaiamana terjadi di
beberapa negara penganut welfare state di Eropa (Ife dan Tesoriero, 2008) Welfare state dianggap
hanya mampu berperan optimal disaat kondisi perekonomian kondusif dan terus tumbuh, sebaliknya di
masa krisis ketika layanan sosial paling dibutuhkan publik welfare state justru mengalami era paling sulit
dalam menyediakan layanan sosial akibat keterbatasan fiscal (Ife dan Tesoriero, 2008). Di tengah krisis
tersebut yang muncul bukanlah usaha kolektif masyarakat untuk berbagi melainkan justru melahirkan
kepelitan sosial yang semakin mengekslusifkan kelompok-kelompok masyarakat. Di beberapa negara
Eropa kebencian terhadap imigran menjadi isu besar yang menjadi konsentrasi partai-partai konservatif
yang menganggap mereka sebagai beban bagi sistem welfare state-nya.
Indonesia sendiri agaknya belum mampu menentukan arah pembentukan welfare state yang mapan.
Hal ini ditunjukan dengan peran negara yang sangat terbatas dalam pelayanan kelompok miskin dan
marjinal. Negara masih berusaha untuk mulai membangun legitimasinya dengan memberikan layanan
kesejahteraan kepada masyarakat bersamaan dengan proses pembangunan yang sedang terus berjalan.
Upaya ini menghadapi dilema serius. Di satu sisi negara memiliki kemampuan finansial yang sangat
terbatas, tetapi di sisi lain kehadiranya dihadapkan pada problematika yang sulit dengan tingginya angka
kemiskinan, kerentanan sosial dan berbagai masalah sosial lainya.
Berbeda dengan welfare state di beberapa negara Eropa yang lahir dari big deal pasca perang yang
menempatkan negara sebagai satu-satunya aktor dominan dalam penyedia kesejahteraan dalam rangka
merekayasa struktur sosial. Kehadiran negara di Indonesia bukanlah satu-satunya aktor yang terlibat
dalam layanan kesejahteraan bagi publik. Bersamaan dengan eksistensi negara telah muncul berbagai
aktor penyedia layanan kesejahteraan sektor informal atau volunteer sector. Victor A Pestoff (2009)
menyebutkan bahwa kehadiran sektor ketiga tidak lain adalah sebagai alternatif yang merupakan
persinggungan dari tiga sektor yang biasa muncul dalam pembahasan welfare regims, yaitu, negara,
pasar dan komunitas. Kehadiran sektor ketiga mencoba menjembatani antara ketiganya dengan
menggali sumber daya dari ketiganya pula serta saling melengkapi dari peran masing-masing.
Potensi penopang kesejahteraan yang tidak bisa dinafikan eksistensinya adalah filantropi. Sigh dalam
Vandendael, Anoux, et all (2013) melihat dalam konteks negara berkembang filantropi menjadi salah
satu bentuk respon terhadap keterbatasan negara yang muncul dari kalangan kelas menengah.
Filantropisme ditandai dengan munculnya berbagai lembaga swadaya masyarakat yang mengandalkan
dana masyarakat baik lokal maupun internasional. Filantropi terbagi menjadi dua tipologi pertama,
filantropi yang berasal dari tradisi giving, kedermawanan yang tercermin dalam kewajiban yang
dimandatkan agama-agama. Dan kedua, filantropi sekuler muncul sebagai respon dari
industrialisasi masif yang menghasilkan kelas menengah yang merasa peduli dengan mereka yang miskin
dan papa (Midgley, 1997). Filantropisme berusaha menggalang kepedulian dan keterlibatan masyarakat
untuk mengalokasikan sumber dayanya untuk melahirkan aktivisme sosial. Salah satu filantropi yang
paling berpengaruh dan paling potensial di Indonesia adalah filantropi religius, khususnya filantropi
Islam (Vandendael, Anoux, et all, 2013).
Studi ini akan menyoroti gerakan kesejahteraan sektor ketiga yang lahir dari komunitas muslim di
Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Filantropisme pada Muhammadiyah seringkali disalah pahami hanya
terkait dengan lembaga amil zakat, infaq dan shadaqah yang hanya menjadi bagian kecil dari sistem
organisasi Muhammadiyah. Pandangan tersebut terlalu terburu-buru dan membuktikan kegagalan
sebagian besar orang dalam melihat konsepsi filantropisme secara luas dan mereduksi konsep
filantropisme hanya pada wilayah pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah. Di sisi lain studi tentang
filantropisme di Muhammadiyah juga belum banyak diulassecara komprehensif, hanya muncul
beberapa tulisan diantaranya oleh Hilman Latif (2010) yang fokus membaca gerakan kesejahteraan
Muhammadiyah, Amelia Fauzia (2012) yang meneliti perkembangan filantropi islam di Indonesia dan
salah satunya adalah yang dilakukan Muhammadiyah khususnya di era kolonial dan orde baru.
Filantropisme sudah sangat kentara dan identik dengan gerakan Muhamamdiyah hanya saja seringkali
studi-studi tentang Muhamamdiyah mendistorsinya dalam bingkai gerakan politik Muhammadiyah
walaupun data-data menampakan peran filantropisnya. Misalnya beberapa studi muhammadiyah yang
dilakukan Alfian (1969), Dien Syamsudin (1991), Syaifullah (1997), Jurdi (2010), dll. Kesemuanya lebih
memotret Muhammadiyah dalam konteks politik sehingga filantropisnya sangat tereduksi. Studi ini
berusaha mengonfirmasi beberapa studi terdahulu tentang gerakan filantropi di Indonesia diantanya:
Studi Hilman Latief (2010) yang berfokus menyoroti filantropisme Muhammadiyah secara keseluruhan
dengan segala kompleksitasnya, Studi disertasi Hilman Latief (2012) yang secara lebih kompleks melihat
seluruh aktor pemberi layanan sosial berbasis ZISWAF di Indonesia yang menunjukan adanya kontestasi
gagasan dan identitas. Studi lain tentang filantropisme adalah disertasi Amelia Fauzia (2013) yang lebih
menyoroti aspek relasi antara negara dan filantropi islam sejak era kolonialisme hingga era modern,
Studi disertasi Widyawati (2011) yang berfokus pada dinamika di balik lahir Undang- Undang Zakat,
Infaq dan Shadaqah serta Undang-Undang Waqaf di era awal reformasi. Selain itu ada studi Julie
Chernov Hwang (2011) yang lebih tidak langsung terkait filantropi tetapi menyoroti tentang aspek
legitimasi negara dalam mewujudkan kesejahteraan yang didalamnya melihat pula kehadiran sektor
ketiga di Indonesia sebagai penopang legitimasinya, sebaliknya di beberapa negara timur tengah
kehadiran sektor ketiga justru berusaha menggerogoti legitimasi negara.
Pendekatan studi kasus historian d ig unakan da l am penul isan s tudi i ni dengan mengedepankan
teori motif dari tradisi gift yang diperkenalkan oleh Alan Page Fiske dalam Komter (2005) yang
menyebut motif gift terdiri dari empat tipe; authority ranking, community sharing, market pricing dan
equality matching. Selain itu, studi ini berusaha melihat teori relasi sektor informal (voluntary sector)
dan sektor formal (negara) meminjam teori Helmke dan Levitsky (2003) yang membagi tipologi
relasi berdasarkan kriteria kesamaan atau perbedaan tujuan sektor formal dan informal, serta
efektivitas negara. Teori ini ditempatkan untuk memotret relasi layanan Muhammadiyah dalam konteks
sosial politik yang dinamis dari berbagai fase pemerintahan. Helmke dan Levitsky (2003) melahirkan
empat tipologi relasi yaitu: akomodatif, kompetisi, komplementer, substitusi.
Indikator efektivitas negara digunakan dua pendekatan pertama, teori Katzeinstein (dalam,
Gourevich, Peter A, et, al, 2008) yang melihat efektifitas negara dalam dua hal, yaitu derajat intervensi
dalam menciptakan kondusifitas di masyarakat, dan kemampuan negara untuk menjaga relasi dengan
aktor diluar dirinya, selain itu RJ. Baum (2011), juga melihat negara dari kemampuan administratif dan
birokratisnya dalam merespon tuntutan publik yang
dinamis.
Pembagian Tipologi relasi Institusi Informal dan formal
Sumber: Helmke dan Levitsky (2003:12)
Filantropisme, Bukan sekedar Derma
Filantropisme secara konsep memang belum matang dan masih jarang diperkenalkan kepada khalayak
umum, walaupun secara praksis tradisi filantropisme sudah melekat hampir di setiap tubuh masyarakat
dari yang paling primitif hingga masyarakat post-industrial yang berbasis pada konsumerisme. Filantropi
memang belum memiliki sebuah batasan yang jelas dan seringkali dikaitkan dengan aspek
kedermawanan, filantropi secara etimologis berasal dari kata “philo” cinta, dan “anthropos” manusia,
yang berarti kepedulian seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain berdasarkan pada
kecintaannya pada sesama manusia (Latief, 2010). Robert Payton (1988) mendefinisikan filantropi
mencakup tiga kegiatan yang saling berhubungan, yaitu; layanan sosial, asosiasi sosial dan derma sosial
bagi kemaslahatan umum. Tujuan filantropi menurutnya dibagi dua, perilaku kasih sayang untuk
menanggulangi penderitaan dan perilaku kemasyarakatan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan.
Pemahaman awam tentang filantropi seringkali cenderung mengaitkanya dengan sekedar proses
charity, yang diambil dari bahasa latin artinya cinta tanpa syarat. Menurut Helmut K. Anheier dan
Regina. A. List, dalam Widyawati (2011) antara Charity dan Filantropi dibedakan dari sisi tujuan
pemberiannya, charitas dimaksudkan sekedar memberikan untuk kebutuhan jangka pendek, sedangkan
filantropi berupaya untuk menyelidiki dan menyelesaikan sebab utama dari persoalan. Beberapa studi
menunjukan bahwa konsep filantropi lebih diarahkan pada model filantropi untuk keadilan sosial yang
mendorong filantropisme tidak sekedar berusaha reaktif terhadap masalah yang di depan mata,
melainkan memerlukan kemampuan untuk mereproduksi lahirnya struktur sosial, ekonomi dan politik
yang lebih menguntungkan mereka yang papa (Hunsaker dan Hanzl, 2005)
Zakat, apakah bagian dari Filantropisme?
Pemahaman filantropisme dalam tradisi islam telah berakar kuat melalui adanya perintah zakat, infaq,
shadaqah dan waqaf (ZISWAF). Zakat merupakan konsep tunggal dalam islam yang menuntut adanya
kewajiban setiap orang muslim untuk menyisihkan sebagian dari hartanya yang sudah memenuhi
kriteria jumlah dan waktu tertentu berdasarkan ketentuan khusus. Sedangkan, Infaq, Shadaqah dan
Waqaf lebih merupakan pilihan yang tidak diwajibkan melainkan dishunahkan (dianjurkan) dalam rangka
kepentingan umum. Zakat dari sisi penerimanya juga sudah memiliki kriteria tersendiri yaitu 8 golongan
yang disebutkan dalam al Qur’an maupun Hadist. Berbeda dengan zakat, konsep infaq, shadaqah dan
waqaf lebih memiliki keleluasaan bagi penerima manfaatnya hanya saja memang lebih ditekankan untuk
memenuhi kebutuhan umum serta melayani mereka yang tidak mampu.
Gregory C. Kozlowski (2006) menyebutkan zakat sebenarnya bukanlah filantropisme yang bermakna
belas kasihan pada manusia lain serta upaya redistribusi aset, melainkan sebuah kewajiban agama yang
dilakukan karena keinginan untuk mendekatkan diri dengan Tuhanya. Konsep ini secara tekstual
memang benar, sebaliknya secara kontekstual zakat tidak bisa semata-mata ditempatkan dalam ruang
kososng secara sosial, proses pelaksanaan zakat selalu terkait dengan pilihan-pilihan rasional seseorang
untuk memberikan pada siapa dan melalui apa dan berapa banyak. Hal ini dikarenakan tidak ada
kewajiban mutlak tentang bagaimana proses pemberian zakat sehingga proses pemberian itu tidak
mungkin dilepaskan dari relasi-relasi kontekstual.Zakat hanya bisa dikeluarkan dari filantropisme ketika
negara hadir dalam sosoknya yang mewajibkan setiap muslim yang memenuhi syarat untuk membayar
zakat melalui negara dengan konsekuensi hukum tertentu bagi yang menolaknya. Sebaliknya apabila
kehadiran zakat cenderung didorong oleh rasa kepedulian baik langsung ataupun secara tidak langsung
lahir dari tuntutan kewajiban teligius maka konsep zakat tidak bisa dilepaskan dari proses filantropisme.
Kewajiban zakat yang dikelola negara pernah diterapkan dalam berbagai masa pemerintahan islam
khususnya di era Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin serta di beberapa era kekhilafahan. Terkait hal ini
Robert D. Mc Chesney menyebutkan zakat menjadi sebuah ambiguitas dalam islam, disatu sisi ia
merupakan kewajiban namun pelaksanaannya sangat tergantung dengan konteks sosial masyarakat,
kadang muncul otoritas kadang dilepaskan begitu saja.3 Menurut Ridwan al Makasary (2006) kondisi ini
dikibatkan proses pengelolaan zakat oleh negara seringkali diwarnai penyalahgunaan sehingga
3 Lihat dalam Robert M. Chesney http://www.learningtogive.org/faithgroups/phil_in_america/ philanthropy_islam -
.asp diakses pada 20 november 2013 pukul 15:27
melahirkan distrush terhadap institusi negara yang memicu para ahli fiqh (hukum syariat) untuk
mendukung distribusi zakat secara intrapersonal.
Di Indonesia pengelolaan zakat telah menjadi tradisi akar rumput. Negara sejak masa kesultanan islam,
kolonial, maupun era orde lama dan orde baru tidak campur tangan dalam pengelolaan zakat (Al
Makasary, 2006; Widyawati, 2011). Zakat biasanya diberikan masyarakat kepada institusi agama di
sekitarnya, mulai dari pengajian, pesantren, sekolah agama, yayasan atau organisasi islam, atau pada
seorang ulama setempat. Dinamika akar rumput ini berjalan dalam tradisi masyarakat Indonesia,
terkadang zakat juga tidak dimaknai sebagaimana mestinya (dihitung dan memenuhi ketentuan khusus).
Tradisi zakat pada masyarakat Indonesia lebih identik dengan sedekah, tetapi dimaknai sebagai zakat
(Latief, 2010). Kurniawati (ed) dalam Widyawati (2011) mengatakan survei PIRAC pada 2000-2004 di
sepuluh kota besar, ditemukan rata-rata masyarakat Indonesia di kota-kota besar membayar zakat
sekitar Rp. 124.000.4 Riset yang dilakukan BAZNAS dan IPB dan IDB menunjukan potensi zakat
masyarakat Indonesia sebesar 217 Trilyun rupiah (Beik, et, al, 2013), walaupun yang tercatat oleh
Baznas pada 2012 baru sebesar 2,2 Trilliyun atau 1% dari total potensinya.5
Wajah Filantropisme Muhammadiyah
Filantropi Islam pada dasarnya merupakan reinterpretasi dari ajaran agama yang menganjurkan derma,
berupa ZISWAF. Selama ini aplikasi dari ajaran ini diterapkan dengan beragam metode dan berbagai
motif baik dilakukan secara indvidu maupun secara kolektif berdasarkan pada konteks budaya
masyarakatnya (Latief, 2013) Persentuhan antara filantropi tradisional dan filantropi modern mulai
membentuk sebuah gerakan baru. Gerakan ini berorientasi menjadikan filantropi sebagai alat untuk
mengentaskan masalah sosial. Hadirnya lembaga filantropis Islam di Indonesia menunjukan adanya
reorientasi menuju model filantropisme modern. Fernandes dalan Vandendael (2013) menyebutkan
bahwa institusionalisasi filantropi Islam di Indonesia muncul sebagai bentuk transisi antara bentuk-
bentuk traditional giving menuju mobilisasi yang berkelanjutan pada sumber daya indigeneous.
Dalam konteks filantropisme islam di Indonesia solidaritas sosial ini terwujud dalam lembaga-lembaga
sektor ketiga yang dibangun atas inisiatif masyarakat. Hilman Latief (2013) menyebutkan di Indonesia
inisiatif masyarakat untuk melakukan pengorganisasian diri telah dilakukan melalui berbagai cara
diantaranya dengan mendirikan lembaga-lembaga sosial baik yang bergerak di bidang pendidikan,
kesehatan dan pelayanan sosial. Keberadaannya tidak hanya memberi nafas dan darah baru bagi
masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan di luar struktur pemerintah, tetapi juga menjadi
alternatif ketika kebutuhan masyarakat lebih besar daripada kapasitas yang dimiliki pemerintah.
Muhammadiyah tidak bisa dilepaskan dalam konteks sosial tersebut, kehadiranya dari latar sejarah yang
kompleks telah melahirkan kesadaran akan pentingnya kolektifisme komunitas muslim dalam
menghadapi kondisi sosial aktual.
4 Bandingkan dengan, Abidin, Naniek dan Kurniawati (ed) dalam Asep Saepudin Jahar, 2010, Masa Depan Filantropi Islam di Indonesia: Kajian Lembaga-Lembaga Zakat dan Wakaf, Annual Conference in Islamic Studies
(ACIS) ke 10, Banjarmasin, 1-4 November, hal:687 menemukan potensi perorangnya Rp. 684.550,- 5 Lihat dalam http://bimasislam.kemenag.go.id/informasi/berita/35-berita/706-menag-terima-laporan-perkemba- ngan-zakat-dari-baznas.html diakses pada 20 november 2013, pukul 17.06
Kehadiran filantropi islam di Indonesia menurut Amelia Fauzia (2013) sudah ada sejak era masa-masa
kerajaan islam, dimana filantropi menjadi penopang bagi lahirnya tradisi dan kebudayaan islam seperti
pesantren-pesantren. Memasuki era kolonialisme Filantropi menjelma menjadi sumber daya sosial yang
dihimpun untuk mendukung perjuangan melawan penjajahan. Kolektifitas ini digerakan kesadaran-
kesadaran lokal yang tumbuh dari kepatuhan dan kecintaan pada para pemimpin lokal yang karismatik
dalam melawan hindia belanda.
Memasuki fase awal modernisme di Indonesia, khususnya ketika fase politik etis diperkenalkan oleh
pemerintah kolonial Hindia belanda pada awal abad 20-an. Saat itu pula lah muncul sebuah tradisi baru
dalam filantropisme islam di Indonesia. Hadirnya politik etis yang cenderung diskriminatif justru
melahirkan keterbalakangan akibat ketidak mampuan komunitas muslim bersaing dalam ruang
modernisasi yang sedang berjalan. Politik etis hanya memberikan akses pendidikan, kesehatan dan
sosial hanya kepada kalangan aristokrat pribumi. Di sisi lain kalangan santri pribumi cenderng menaruh
kecurigaannya pada usaha modernisasi sehingga terjebak pada kejumudan ilmu pengetahuan dan makin
terpinggir dari kemajuan.6
Filantropisme islam di awal abad ke 20, mulai tumbuh bersamaan dengan munculnya tren pembaharuan
dan modernisasi agama sebagai pengaruh dari revivalisme islam di kawasan Timur Tengah. Pada fase
inilah Muhammadiyah dilahirkan melalui sosok KH. Ahmad Dahlan, seorang yang memiliki peran yang
kompleks baik sebagai anak penghulu keraton yang sempat mengenyam pendidikan di Timur Tengah,
sekaligus seorang aktivis pergerakan baik Syarikat Islam, Jamiatul Khoir, maupun Boedi Oetomo (Jurdi,
2010).
KH. Ahmad Dahlan membentuk gerakan Muhammadiyah sebagai gerakan multi sektoral yang bersifat
ortodoksi dan otopraksi. Muhammadiyah berusaha melakukan pemurnian agama sekaligus juga
melakukan pembaharuan praktek-praktek aktivisme sosialnya. Muhammadiyah membentuk berbagai
majelis yang spesifik untuk menangani berbagai permasalahan umat. Pilihan ini tidak lepas dari
rasionalisasi konteks sosial politik yang melatar belakangi kelahiranya. Muhammadiyah muncul tidak
sekedar sebagai gerakan dakwah islam, melainkan berusaha untuk membangun fondasi gerakan
pembaharuannya secara komprehensif melalui berbagai program-program yang terorganisir. Adabi
Darban (2000) menyebutkan bahwa ajaran KH. Ahmad Dahlan meliputi:
1. Membersihkan aqidah islam dengan mengembalikan kemurnian keyakinan dan pengabdian
kepada Allah SWT, sebagai landasan pokok agar umat tidak terjebak pada syirik.
2. Mengembalikan seluruh ajaran islam pada pokok hukumnya yaitu, Al Quran dan Shunah Nabi
Muhammad saw, khususnya dalam ibadah
3. Memperbaiki pengajaran dan pendidikan islam serta penyebaran kebudayaan islam
4. Menghidupkan semangat ukhuwah islamiyah pada bidang politik, sosial dan ekonomi
6 Belanda hanya mendukung sistem pendidikan untuk elit pribumi dan dengan salah paham menghindari islam yang dianggapnya berpotensi melawan, sedangkan komunitas muslim bersikap antipati karena trauma konflik / perang berkepanjangan melahirkan anti terhadap segala yang berbau tradisi barat termasuk pakaian, gaya hidup, cara-cara dan ilmu pengetahuannya lihat Yudi Latif, 2005, Intelegensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad 20, Mizan: Bandung,
5. Membendung aktivitas zending Kristen dan misi Katolik yang dibawa oleh kolonialisme
Pembaharuan Muhammadiyah salah satunya dilakukan dengan mendorong perubahan kultural tentang
pembayaran zakat. Muhammadiyah mendorong pengumpulan zakat untuk disalurkan kepada fakir
miskin, padahal sebelumnya zakat dibayarkan pada para tokoh agama setempat dan dijadikan
pendapatan bagi mereka (Mitsuo,1983). Dorongan untuk berzakat, ataupun bersedekah inilah yang
memunculkan semangat pada anggotanya untuk mendermakan uang, tenaga bahkan mewakafkan
kelebihan aset berupa tanah atau rumah untuk mendirikan berbagai fasilitas pelayanan Muhammadiyah
di daerahnya masing-masing. Hampir semua fasilitas yang didirikan Muhammadiyah di era awal
perkembangannya adalah dukungan penuh dari anggotanya. Alfian (2010:218) mencatat pada periode
1923 pendapatan Muhammadiyah di Jogjakarta sebesar f 64,737.59 dengan komposisi 1 % dari iuran
anggota, 37 % dari donasi, 8% dari zakat, 12,5% dari subsidi, 13,5% dari jasa pendidikan dan dari
perusahaan 8%. Proporsi dana donasi dan zakat menjadi pos pendapatan terbesar bagi aktivisme
Muhamamdiyah.
Gerakan Muhammadiyah mendapat sambutan antusias di kalangan umat islam khususnya komunitas
kelas menengah baik dari kalangan pedagang, pengrajin dan pamong praja. Komposisi anggota
Muhammadiyah yang didominasi kelas menengah menjadikannya berkembang di kota-kota utama di
Jawa dan Sumatera seperti Yogyakarta, Pekalongan, Solo, Kudus, Semarang, Cilacap, Malang, Surabaya,
Lumajang, Jakarta dan Padang. Deliar Noer (1982) menyebutkan pada 1925, Muhammadiyah telah
mempunyai 29 cabang dengan 4000 orang anggota. Pada periode ini Muhammadiyah sudah mampu
membangun banyak fasilitas di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan, diantaranya 8 HIS, 1
Kweekschool, 32 Standardschool, 14 Madrasah, 2 Klinik, 1 Rumah Miskin dan 2 Rumah Yatim. Pada
periode 1937 sudah terbentuk 921 cabang di seluruh Indonesia: Jawa-Madura sebanyak 401 cabang,
Sumatera sebanyak 368 cabang, Sulawesi sebanyak 105 cabang, Kalimantan 33 dan lainnya 14 cabang
(Jurdi(ed), 2010:80). Pada dekade awal berdirinya keanggotaan Muhammadiyah juga menunjukan
pertumbuhan yang sangat pesat. Deliar Noer (1982:95) memperkirakan pada 1921 anggotanya baru
mencapai 597 orang dan meningkat pesat pada 1925 sebesar 4000 orang dan pada 1930 menjadi 24000
dan 1935 sudah mencapai 43000 dan 1938 mencapai 250.000 orang.
Eksistensi layanan kesejahteraan berbasis filantropis yang diberikan Muhammadiyah pada masa itu
mampu melahirkan pengaruh dan legitimasi sebagai patron bagi kalangan pribumi. Muhammadiyah
dianggap masyarakat mampu memberikan alternatif akses kebutuhan akan layanan pendidikan,
kesehatan dan sosial bagi kaum pribumi yang tersingkir. Layanan pendidikan bagi kaum pribumi
memang telah disediakan tetapi kebijakan pemerintah memilih mempertahankan stratifikasi sosial
menjadikan kebijakan tersebut berorientasi pada pemecahan kelas yang membatasi akses layanan
pendidikan berkualitas hanya untuk anak-anak kaum aristokrasi pribumi. Adapun kalangan pribumi kelas
menengah dan rendahan hanya mendapatkan akses volkschool (sekolah rakyat). Dalam konteks ini
lahirlah motif authority ranking yang direproduksi dalam layanan kesejahteraan Muhamamdiyah yang
berusaha berusaha melahirkan garis hirarkis dalam struktur masyarakat malalui pembentukan kuasa,
kewibawan, populisme, dan pembuktian-pembuktian prestasinya.7 Sikap ini ditujukan untuk memastikan
bahwa mereka yang paling atas memiliki otoritas untuk mendorong inisiatif serta memobilisasi sumber
daya yang diatasnamakan seluruh bagian dari komunitas masyarakat pribumi.
Patronase dan legitimasi yang diterima masyarakat terhadap Muhammadiyah tidak dijadikan wahana
membentuk stratifikasi kuasa baru. Sebaliknya patronase ini muncul seiring dengan lahirnya
kewibawaan Muhammadiyah untuk memobilisasi dukungan masyarakat. Egbert Harmsen (2008)
menyebutkan bahwa pengalaman relasi civil society dan negara di Yordania mammpu melahirkan
patronase bertingkat. Pola patronase ini terbentuk justru dengan lahirnya civil society yang dengan
sengaja diberikan celah oleh negara untuk tampil. Negara mendapat keuntungan dengan menjadi
puncak dari patronase tersebut sedangkan civil society yang lahir cenderung tampil untuk memperkuat
legitimasi negara dengan membentuk patronase terbatas di masyarakat. Hal ini seperti pula
diperlihatkan oleh Julie Chernov Hwang (2011) ketika negara efektif maka civil society yang lahir mampu
terikat dalam sistem korporatiknya untuk memperkuat legitimasinya dihadapan publik. Negara akan
cenderung memberikan dukungan terbatas untuk mempertahankan relasinya dengan civil society yang
bersangkutan.
Perbedaan mencolok antara patronase civil society di Yordania dengan Muhammadiyah pada fase ini
adalah inisiatif kemunculannya yang berasal dari masyarakat sebagai reaksi counter atas dikriminasi
negara. Sedangkan di Yordania civil society muncul dari insentif yang diberikan negara. Reaksi counter ini
menjadikan relasi Muhamamdiyah dan negara semata-mata dalam rangka mempertahankan dukungan
atas aktivismenya. Di sisi lain, Muhammadiyah berusaha secara rapi menyimpan sebuah agenda
tersembunyi untuk melawan agenda negara kolonial. Strategi ini diwujudkan dengan upayanya untuk
membangun gerakan yang bersifat populis sebagai sarana menarik simpati komunitasnya untuk
memberikan dukungan sekaligus bergabung sebagai anggotanya. Dukungan tersebut diartikulasikan
Muhammadiyah sebagai representasi sikap pribumi untuk berhadapan dengan negara kolonial.
Muhammadiyah berhasil menerobos keterbatasan negara dengan memperkuat pengaruh gerakannya
dihadapan kaum pribumi sekaligus dalam waktu bersamaan menarik dukungan negara terhadapnya.
Inisiatif Lokal di tengah Absesnya Negara (Kolonial)
Di tengah kebijakan modernisasi terbatas selama era politik etis pemerintah kolonial berusaha
mendorong gerakan misi gereja untuk bergerak di wilayah jajahan dalam menyediakan layanan
pendidikan, sosial dan kesehatan. Negara Kolonial Hindia Belanda secara terbuka menyatakan
kebijakannya netral agama, tetapi sulit dipungkiri peran mereka dalam mendukung gerakan misi gereja.
Pada prakteknya sejak 1810 Raja William I mengeluarkan dekrit untuk mendukung gerakan misi ke
Hindia dengan memberikan kewenangan otonom langsung di bawah gubernur jendral dan mendapat
dukungan dari negara berupa subsidi, sumbangan finansial dan pembebasan pajak (Shihab, 1997:39-40).
Puncaknya pada 1901 dibawah perdana menteri Abraham Kuyper, Ketua Partai Kristen Anti Revolusi
yang berhasil mengalahkan kubu liberal yang telah berkuasa hampir setengah abad. Pada 1902. Kuyper
menunjuk Alexander Idenburg (seorang politisi Kristen ortodok dan konservatif) untuk menjabat
7 Lihat definisi authority ranking dalam Alan Page Fiske, dalam Aafke Komter (2005) Social Solidarity and the Gift, Cambridge : Cambridge University Press,
Menteri Urusan Kolonial yang mengeluarkan kebijakan untuk memberikan dukungan besar-besaran
kepada misi Kristen dan Katholik (Shihab, 1997).
Belanda memiliki rasionalisasai dengan mendukung aktivitas gerakan misi kristen pada pribumi akan
cenderung mengamankan posisinya di Hindia yang sedang dimodernisasi untuk dipersatukan di bawah
Kerajaan Belanda (Shihab, 1997). Kebijakan ini menurut Snouck Hurgronje lahir akibat adanya ketakutan
yang berlebihan pemerintah terhadap pribumi dan islam, terutama akibat perlawanan yang panjang di
berbagai daerah sekaligus ketidak pahaman pemerintah kolonial terhadap islam dan budayanya.
Ketakutan ini diartikulasikan dengan usaha untuk mematikan pertumbuhan islam dan menolak
modernisasi sekolah tradisional islam yang dianggap bisa memelihara musuh-musuh negara.8 Praktek
ini sempat dijadikan sasaran kritik partai sosialis Belanda yang menyebut adanya upaya “Kristenisasi
yang dipaksakan” di Hindia dan penyalahgunaan fasilitas negara oleh gerakan misi (Shihab, 1997:88-89).
KH. Ahmad Dahlan memandang serius dua persoalan menyangkut kaum pribumi. Pertama, adanya
barier dengan kebijakan legal diskriminatif yang dilakukan negara sehingga memaksa mayoritas populasi
pribumi muslim tidak mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai.9 Kedua, adanya
potensi ancaman dari masifnya pengaruh gerakan misi Katolik dan Zending Kristen yang dengan
dukungan penuh pemerintah mampu menyediakan layanan pendidikan, sosial dan kesehatan.
Aktivisme sosial gerakan misi gereja dianggap sebagai upaya serius untuk menjauhkan masyarakat
pribumi terhadap islam. Negara kolonial Hindia Belanda dan Gereja melakukan perselingkuhan
kepentingan yang berorientasi untuk mengubah struktur dan kultur masyarakat Hindia. Upaya negara
dan sekaligus gerakan gereja untuk melakukan layanan sosial bagi pribumi tidak lain menciptakan
legitimasi dan penanaman pengaruh sosial di kalangan pribumi untuk menciptakan masyarakat pribumi
baru yang pro Hindia Belanda. Upaya ini dinilai berpotensi meruntuhkan legitimasi tradisional utamanya
kalangan para santri muslim. Vanderbosh dalam Shihab (1997) mencatat sejak 1909-1912 terjadi
peningkatan 40% fasilitas pendidikan gerakan misi akibat adanya dukungan finansial pemerintah. Hal ini
mendorong peningkatan partisipasi pribumi sebesar 20% di sekolah-sekolah swasta milik gerakan misi.
Muhammadiyah berusaha menghadapi gerakan misi gereja dengan membangun fasilitas tandingan
untuk bersaing memperebutkan pengaruh di kalangan pribumi. Perebutan pengaruh ini pada dasarnya
berusaha menunjukan spirit bahwa kaum pribumi mampu maju dengan upaya kolektifnya sehingga
tidak mudah terpengaruh oleh pemberian-pemberian komunitas gereja yang didukung oleh negara.
Sikap ini terwujud dalam diri KH. Ahmad Dahlan yang selalu menyerukan perlunya pembaruan sikap
8 Snouck Hurgonjee mengkritik keras kebijakan pemerintah kolonial Hindia belanda yang mengandung ketakutan berlebihan dengan komunitas musim dan memberikan rekomendasi untuk menerima islam sebagai kultur dan mewaspadainya sebagai kekuatan politik. Lihat Yudi Latif ,2005, Intelegensia Muslim dan Kuasa: Genealogi intelegensia Muslim Indonesia Abad 20. Hal 82-84 9
Terdapat dua jenis diskriminasi, pertama, legal diskriminasi, yaitu sebuah kehendak sadar yang dilakukan negara
untuk meminggirkan suatu kelompok dari akses-akses dan fasilitas sosial, ekonomi dan politik yang tercermin dalam
sebuah legal formal (hukum), Kedua, sosial diskriminasi, yaitu, munculnya status warga kelas dua yang terpinggirkan akibat adanya perbedaan terhadap akses sosial, politik dan ekonomi, tidak tercermin dalam hukum
formal tetapi menjadi rasionalisasi kebijakan, lihat Dixon, John dan Robert P. Scheurrel (ed.), 1995. Social Welfare in Indigenous People, London : Routledge, hal ix
dikalangan komunitas muslim untuk bisa menerima kemajuan dan mengambil spirit sosial yang
terkandung dalam surat Al Maun.10 KH. Ahmad Dahlan menafsirkan surat Al Ma’un sebagai keharusan
untuk mewujudkan pelayanan sosial untuk menolong kaum dhuafa melalui gerakan amal shaleh yang
nyata secara sosial. Beliau memandang pentingnya umat islam untuk saling tolong menolong sesamanya
“self helping”. Lahirnya kolektifitas dan solidaritas umat diharapkan mampu memberikan kekuatan
untuk meraih posisi yang setara dengan kelas pribumi atas dan bahkan bangsa Eropa. M. Yusron dalam
Shihab (1997) menyebutkan KH. Ahmad Dahlan selalu mengulang-ulang pelajarannya tentang surat Al
Ma’un sebelum para muridnya melaksanakan aktivitas sosial.
Perebutan legitimasi ditengah kebijakan diskriminatif sekaligus rasa apriori kepada netralitas kekuasaan
melahirkan kecenderungan membentuk perjuangan politik identitas kaum pribumi. Syafi’i Ma’arif (2012)
menjelaskan politik identitas dikaitkan dengan kepentingan anggota-anggota sebuah kelompok sosial
yang merasa diperas dan tersingkir oleh dominasi arus besar dalam sebuah bangsa atau negara. Politik
identitas selalu identik dengan lahirnya pandangan entonasionalisme, dalam kaitannya dengan
Muhammadiyah ia muncul dari perasaan ingin bebas dari kolonialisme yang dianggap sekuler ataupun
dekat dengan gereja dan membentuk sebuah masyarakat baru Hindia yang religius dan berkemajuan.
Muslim Abdurahman (dalam Boy Ztf, Pradana, M. Hilmi Faiq dan Zulfan Barron (ed), 2008) menyamakan
awal munculnya gerakan Muhammadiyah dengan semangat perlawanan kaum bawah di Eropa sejak
pertengahan abad 19, yang oleh George Rode, Eric Hobsbrown dan Edward Thomson disebut sebagai
moral economy, yaitu sebuah gerakan perlawanan arus bawah yang mengakar sangat dalam dari tradisi
dan budaya setempat termasuk perasaan yang muncul dari tradisi agama tentang ketidakadilan. Muslim
Abdurahman (dalam Boy Ztf, Pradana, M. Hilmi Faiq dan Zulfan Barron (ed), 2008) menambahkan
rasionalitas gerakan Muhammadiyah lebih dipengaruhi sentimen kesadaran agama yang dianggap
pengikutnya lebih murni dibandingkan kepentingan mobilitas kelas sosial tertentu. Pengaruh ini yang
memungkinkannya lebih sensitif dengan persinggungan isu-isu keagamaan.
Persaingan antara Muhammadiyah dengan gerakan misi dan zending lahir secara simultan akibat adanya
kebijakan negara. Gerakan misi dan zending tumbuh dari adanya insentif subsidi dan pemberian otoritas
yang besar dari negara. Sedangkan, Muhammadiyah lahir sebagai reaksi atas kebijakan negara yang
dianggap diskriminatif. Situasi ini menciptakan kondisi dimana Muhammadiyah tidak secara langsung
berhadap-hadapan dengan negara. Negara pada dasarnya memiliki kemampuan yang cukup untuk
menciptakan usaha penyediaan layanan hanya saja rasionalisasi kebijakan yang dimilikinya menjadi
penghambatnya untuk terlibat. Hambatan ini menjadikan kehadiran negara cenderung tidak efektif
untuk menyediakan layanan kesejahteraan.
Keberadaan amal usaha Muhammadiyah di berbagai bidang tidak terlepas dari visi organisasi yang anti
kolonialisme dan pro pembaharuan. Di bidang pengajaran, pembentukan sekolah tidak semata-mata
untuk bersaing dengan sekolah-sekolah negeri yang didirikan pemerintah Kolonial ataupun sekolah misi
swasta yang dilahirkan gerakan misi, melainkan ada maksud penanaman visi pembaharuan agama islam
10 Surat ke 107 dalam Al Qur’an isinya : “Tahukah kamu siapa pendusta agama? Mereka itu orang yang menghardik anak yatim, dan mereka yang tidak menganjurkan memberi pada orang miskin, dan celakalah orang yang lalai dalam shalatnya, yaitu orang yang ria dan enggan member bantuan”
sekaligus penanaman nilai-nilai kebangsaan pada masyarakat. Mitsuo (1983:110) menyebutkan secara
diam-diam pada akhir 1930-an sekolah Muhammadiyah menghasilkan sejumlah besar pemuda-pemudi
yang bisa baca tulis, nasionalis fundamental, punya keyakinan agama, bisa menyesuaikan dengan
kondisi ekonomi modern dan terdidik dalam kegiatan organisasi. Modernisasi sekolah yang dilakukan
Muhammadiyah dengan menerapkan pencampuran pelajaran-pelajaran umum dan agama serta bahasa.
Sekolah Muhammadiyah mengajarkan bahasa Melayu (bahasa Indonesia), bahasa Arab sebagai
pelajaran khusus dan bahasa Belanda. Selain itu ilmu umum, seperti Biologi, ilmu pasti (matematika),
ilmu bumi, dan lain-lain diajarkan dengan satu nilai bahwa pelajaran ini penting untuk membaca ayat-
ayat Tuhan di alam semesta (qauniyah).11 Keunggulan lain sekolah Muhammadiyah adalah keterbukaan
aksesnya untuk semua kalangan, tidak seperti sekolah negeri yang masih sulit menerima murid di luar
anak bangsawan dan pegawai pemerintah (Mitsuo, 1983).
Misi pembaharuan agama dan perlawanan juga tampak dalam bidang sosial dan kesehatan dengan
berdirinya bidang Penolong Kesengsaraan Oemom (PKO). PKO diawali terbentuknya tim penolong untuk
menangani korban meletusnya Gunung Kelud pada 1918. PKO pada 1921 diakui sebagai bidang khusus
di Muhammadiyah. Pada 1921, PKO memberikan bantuan pada korban kebakaran di Yogyakarta, 1922
didirkan rumah yatim pertama, klinik yang paling pertama dibentuk adalah PKO di Yogyakarta (1921),
PKO Kota Gede (1925), disusul kemudian klinik di Solo (1929), Malang (1929) dan Surabaya (1930).
Klinik-klinik ini didirikan ditujukan utamanya yaitu menolong mereka yang sakit, namun ada tujuan lain
yang menyertainya, Pertama, menantang model pengobatan tradisional, agar orang yang sakit tidak
pergi ke dukun atau melakukan ritual-ritual untuk penyembuhan (Mitsuo,1983:111). Kedua, klinik ini
dimaksudkan untuk menandingi keberadaan klinik-klinik yang dibangun oleh misionaris Katolik dan para
zending Kristen. Selain membidangi kesehatan PKO juga membidangi urusan sosial lainnya, seperti yatim
piatu dan santunan warga miskin. Eksistensi layanan tersebut memperkuat legitimasi Muhammadiyah
dihadapan komunitas pribumi.
Tujuan yang tersembunyi di balik layanan Muhammadiyah secara garis besar bisa dilihat dalam dua hal,
pertama, upaya untuk melakukan kritik ke dalam komunitasnya utamanya terkait tradisionalisme yang
dianggap bertentangan dengan ajaran agamanya dan menciptakan keterbelakangan, dan kedua,
merupakan upaya bersaing dengan pihak eksternal yang berseberangan tujuan tetapi memiliki cara-cara
ampuh yang ditirunya. Muhammadiyah mengembangkan aspirasi yang berbeda dengan tujuan layanan
yang diberikan negara kolonial. Tujuan pelayanan sosial negara kolonial sebatas memenuhi kebutuhan
administratif dan mempertahankan stratifikasi sosial di masyarakat Hindia (Latif:2005). Sedangkan,
Muhammadiyah berupaya memperkuat kaum pinggiran (pribumi non aristokrat) yang tak mendapatkan
akses untuk bisa tampil setara. Bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda sekolah dan rumah sakit
pemerintah selalu menjadi alat bagi proses sekulerisasi dan pembaratan kaum pribumi. Sedangkan
11 Dinamika sekolah muhammadiyah memadukan antara kecakapan pergaulan dengan pengenalan bahasa untuk
pergaulan dengan berbagai kelas sosial sekaligus modifikasi pengajaran dengan memberikan pelajaran Ilmu non agama sebagai bentuk reinterpretasi tentang tuntutan ajaran agama untuk memahami hakikat dari sunatullah – hukum tuhan dalam alam semesta-, selengkapnya Lihat Nakamura Mitsuo, 1983, Bulan Sabit Muncul Dibalik
Beringin: Studi tentang Pergerakan Muhammadiyah di Kota Gede, Yogyakarta : Gajah Mada, hal: 107-109
Muhammadiyah menjadikannya sebagai fasilitas pembentukan semangat etnonasionalisme-religius dan
penguatan nilai-nilai agama islam yang berorientasi pada pembaharuan dan kemajuan.
Muhammadiyah dan misi Gereja menjadi dua aktor diluar negara yang saling bersaing untuk saling
memperebutkan legitimasi. Kedua aktor non-state yang saling bersaing ini cenderung berusaha
mempertahankan hubungan baiknya dengan negara untuk memastikan keduanya didukung baik secara
finansial maupun regulasi politik agar tetap dibiarkan melaksanakan aktivismenya. Posisi ini ditunjukan
dengan kedekatan KH. Ahmad Dahlan dan kepiawaiannya dalam menjalin relasi dengan pemerintah
kolonial dan pihak misi gereja sekaligus.
Negara dalam kapasitas terbatas cenderung mengapresiasinya reputasi Muhammadiyah dengan
mengakui dan mensubsidi fasilitas sosial yang dimilikinya. Pemerintah kolonial pada memberikan subsidi
kepada Muhammadiyah sebesar f 12916,40 untuk PKO dan f 50377,05 untuk bidang pengajaran
(Darban, 2000; Amelia Fauzia, 2013;Jurdi (ed), 2010). Subsidi ini tidak sebanding dengan subsidi yang
diberikan kepada Katholik dan Kristen. Sekolah Muhammadiyah yang disubsidi pemerintah hanya 112
sekolah dari 416 sekolah yang dimilikinya, sedangkan katholik dan protestan semua sekolahnya disubsidi
dengan masing-masing berjumlah 696 sekolah dan 1.893 sekolah (Jurdi (ed), 2010). Alfian (2010)
menyebut pada 1926 Muhammadiyah hanya mendapat 1,5% subsidi pemerintah Hindia Belanda
sebesar f 579,354.86, sedangkan total subsidi yang diberikan pemerintah kepada swasta sebesar f
7,266,000. Subsidi ini ternyata bagi Muhammadiyah cukup memadai sekitar 15% dari total pemasukan
dana persyarikatan.
Pemerintah kolonial memiliki beberapa pertimbangan penting untuk mempertahankan dukungannya
pada Muhammadiyah, pertama, Muhammadiyah telah menjadi wadah aspirasi sosial bagi kaum pribumi
muslim sehingga menghalanginya sama artinya memancing radikalisasi dan perlawanan kolektif pribumi
muslim yang sangat kuat. Kedua, Sikap Muhammadiyah yang sangat kooperatif sangat dibutuhkan oleh
pemerintah kolonial untuk menghadang radikalisasi pribumi oleh organisasi politik radikal seperti SI
maupun ISDV (Partai Komunis). Ketiga, Kolonial cukup memiliki kepercayaan diri bahwa Muhammadiyah
tetap tidak mampu mengubah status quo dikarenakan kapasitasnya yang masih sangat terbatas.
Relasi antara negara yang tidak efektif dan adanya sektor ketiga yang mengemban misi berbeda
melahirkan adanya relasi kompetisi. Helmke dan Levitsky (2003) melihat dikala negara tidak memiliki
kapasitas yang cukup efektif disatu sisi muncul aktor informal yang memiliki tujuan yang berbeda maka
akan terjadi kompetisi. Aktor informal itu bisa berupa clientelism, patrimonials, clan politics, dan
lainnya. Robert Price dalam Helmke dan Levitsky (2003) menemukan apa yang terjadi di Ghana dimana
administrasi layanan publik yang mahal menjadikan adanya pembatasan bagi rata-rata masyarakat yang
tak mampu, akibatnya muncul institusi tandingan yang muncul dari kultur masyarakat lokal untuk
bersaing memperebutkan legitimasi dengan negara.
Ilustrasi Hubungan Muhammadiyah, Negara Kolonial dan Gerakan Gereja
Negara Kolonial
Elit Pribumi
Misi Gereja
Kelas menengah
dan bawah
Muhammadiyah
Kompetisi yang dilakukan Muhammadiyah dan negara kolonial berlangsung dalam dua ranah yang
masing-masing dengan pendekatan strategi berbeda. Pertama, ranah Muhamammadiyah vis a vis
negara. Kompetisi ini diwujudkan dengan adanya perbedaan aspirasi tujuan dan gagasan yang
merasionalisasi lahirnya layanan kesejahteraan. Muhamamdiyah melakukan kompetisinya secara
tertutup artinya tidak secara frontal melawan negara melainkan membangun hidden agenda yang
merepresentasikan sikap perlawanannya sekaligus merangkul negara di permukaan. Hal ini diperkuat
dengan adanya keterlibatan para pemimpin Muhammadiyah dalam aktivitas politik Syarekat Islam yang
sangat frontal melawan kolonialisme. Kedua, ranah Muhammadiyah vis a vis quasy negara “Gereja”,
Muhammadiyah menunjukan sikap bertentangan dengan mencoba menghadang gerakan misi gereja
dengan model yang fair, yaitu bersaing untuk menyediakan layanan untuk komunitas pribumi sekaligus
bersaing untuk mendapatkan dukungan negara. Pilihan strategi ini terbukti berhasil mereproduksi
banyak amal usaha Muhammadiyah tanpa menimbulkan konfrontasi antara Muhamamdiyah dan misi
gereja secara fisik atau memicu konflik horizontal di masyarakat. Sebaliknya KH, Dahlan justru dikenal
dekat dengan kalangan gereja dan berani untuk melakukan diskursus dengan para pendeta dan pastur.
Di masa kepemimpinannya hampir tidak ada konflik terbuka yang terjadi antara kedua belah pihak.
Sikap Pragmatisme Kolaboratif di bawah Rezim Militer Jepang
Sikap taktis dan pragmatis Muhammadiyah dalam memanfaatkan celah kekuasaan terus
dipertahankannya pasca jatuhnya rezim kolonial Belanda pada Bala tentara Jepang, Jepang tetap
memandang Muhammadiyah sebagai mitra strategis untuk mendukung legitimasi propaganda
politiknya. Muhammadiyah diberi keleluasaan dengan prasyarat ia tunduk pada tujuan pendirian Asia
Raya di bawah pimpinan Jepang dan melaporkan seluruh kegiatan dan administratif organisasinya.
Mitsuo (1983:126) juga menyebutkan Jepang memanfaatkan islam sebagai kekuatan anti barat dengan
menempatkannya sebagai salah satu pilar propagandanya. Para elit Muhammadiyah dimanfaatkan
untuk memobilisasi kekuatan rakyat. KH. Mas Manshur ketua PP Muhammadiyah saat itu ditunjuk untuk
menjadi tiga serangkai pemimpin PETA (Pembela Tanah Air) (Jurdi, 2010:109). Elit Muhammadiyah di
berbagai daerah serta para guru-guru sekolah Muhammadiyah juga banyak dijadikan pemimpin untuk
gerakan-gerakan para militer Jepang (Jurdi (ed), 2010). Jepang juga memberikan kesempatan para tokoh
muslim untuk membentuk Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) sebagai wadah aspirasi politik
umat islam.
Pemerintah bala tentara Jepang tidak memprioritaskan pembangunan kesejahteraan sosial.
Kebijakannya hanya berfokus pada mobilisasi dukungan untuk menghadapi perang pasifik. Pendidikan
lebih diarahkan untuk menanamkan doktrin Asia Timur Raya. Dalam kondisi ini peran penyediaan
pendidikan dan kesehatan tetap dilakukan Muhammadiyah. Muhammadiyah menolak doktrin-doktrin
Jepang, khususnya yang dianggap bertentangan dengan ajaran islam yaitu menolak seikirei atau hormat
ke arah timur pada teno heika (kaisar Jepang). Muhammadiyah mengimbanginya dengan membentuk
kesatuan tabligh khusus yang diterjunkan di seluruh Jawa dan Madura untuk melakukan propaganda
nasiolisme religius yang dibalut dakwah untuk melawan doktrin Jepang yang dianggap menjauhkan
rakyat dari islam. Sekolah-sekolah dan kantor-kantor Muhammadiyah dijadikan pusat pengorganisasian
yang aman karena secara formal Muhammadiyah mendapat jaminan pemerintah (Jurdi, 2010:118).
Kebijakan perang Jepang di sektor pertanian hanya fokus pada pemenuhan pasokan perang sehingga
menimbulkan kemiskinan, kelaparan dan penderitaan rakyat (Kurasawa, 1993). Ketidak efektifan
pemerintah jepang dalam menyediakan akses pendidikan tidak bisa dimanfaatkan secara signifikan oleh
Muhammadiyah dikarenakan Muhammadyah juga mengalami periode yang sulit dimana ruang gerak
organisasinya selalu dibatasi. Pemerintah hanya mengizinkan kegiatan dan aktivitas rutin yang tidak
bertentangan dengan kebijakan politiknya. Muhammadiyah diuntungkan dengan relasi akomodatifnya
dengan Jepang. Filantropis Muhammadiyah diwujudkan secara sporadis dengan membagian makanan
dan sandang kepada fakir miskin di berbagai daerah (Lucas, 2004). Kedekatan elit Muhammadiyah dan
pemerintah Jepang dimanfaatkan untuk menghimpun dan mengamankan pasokan bahan pangan dan
sandang untuk didistribusikan pada kaum pribumi yang membutuhkan.
Buaian Politik dan Perjuangan Politik Awal Kemerdekaan
Pada periode awal kemerdekaan keterlibatan Muhammadiyah dalam pelayanan sosial tidak terlihat
dengan jelas. Muhammadiyah dan negara sama-sama berada dalam situasi yang sulit menghadapi
revolusi kemerdekaan. Muhamamdiyah pada periode ini setidaknya memainkan beberapa peran.
Pertama, peran politiknya dengan ikut serta mendirikan Partai Masyumi pada 1945 yang merupakan
partai gabungan dari seluruh organisasi muslim saat itu. Peran politik itu mampu mendukung upaya-
upaya diplomatik dan pembangunan negara melalui tokoh-tokoh Muhammadiyah di pemerintahan.
Kedua, peran perjuangan fisik melawan agresi militer belanda melalui para anggotanya yang
meleburkan diri ke Hizbullah, dan Ketiga, Muhammadiyah berusaha mempertahankan seluruh fasilitas
pendidikan dan kesehatannya dan dukungan finansial untuk perjuangan fisik. Amelia Fauzia (2013)
menyebutkan pada fase perjuangan kemerdekaan filantropisme dari dana ziswaf lebih banyak terkuras
untuk mendanai jihad dalam rangka perang kemerdekaan. Jihad ini dilakukan kalangan muslim
mengorganisir diri untuk mempertahankan kemerdekaan dalam wadah Hizbullah yang diinisiasi para
tokoh Masyumi di berbagai daerah.
Pasca perjuangan revolusi kemerdekaan Muhammadiyah masih dihadapkan pada fase yang sulit dalam
dinamika politik. Muhammadiyah yang terlibat dalam Masyumi lebih fokus memperjuangkan gerakan
politiknya dari level elit hingga akar rumput yang ditunjukan dengan mobilisasi politik anggotanya untuk
memenangkan Masyumi pada pemilu 1955. Pasca Pemilu 1955, pergulatan elit tentang dasar negara di
konstituante menjadi fokus perhatian yang juga menyita energi akar rumput untuk memobilisasi
dukungan ekstra parlementer.
Pasca dibubarkannya konstitunate pada 1959, Soekarno menerapkan kebijakan demokrasi terpimpin
yang berpayung pada gagasan Nasionalisme, Sosialisme dan Agama (NASAKOM). Muhammadiyah
sebagai bagian dari Masyumi mengambil jalan bersebrangan dengan gagasan tersebut yang
menimbulkan ketegangan dengan rezim. Puncaknya Muhammadiyah mengalami ketegangan dengan
negara pasca dibubarkannya Masyumi pada 1960. Masyumi (dan juga PSI) dibubarkan akibat para
tokoh-tokohnya terbukti terlibat dalam gerakan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) /
Persmesta (Perjuangan Rakyat Semesta) yang menuntut penerapan otonomi daerah. Di sisi lain
ketegangan politik ideologis antara Muhammadiyah dengan PKI (pengusung utama Nasakom)
menjadikan Muhammadiyah sebagai sasaran empuk bagi provokasi komunis yang menyebut
Muhammadiyah sebagai kontra revolusioner dan sebagai sarang eks-eks partai ‘terlarang’ Masyumi. PKI
menuntut Soekarno untuk membubarkan Muhammadiyah.
Di tengah konflik politik yang terus terjadi Muhammadiyah memainkan fungsi politik taktisnya dengan
merangkul salah satu elemen kekuatan negara. Muhamamdiyah membangun kemitraan strategis
dengan Angkatan Darat (AD) yang anti komunis. Para pemimpin Muhammadiyah memanfaatkan
kedekatannya dengan para pemimpin AD yang eks Hizbullah dan eks Peta. Simbiosis ini terbukti dengan
kesediaan Jendral AH. Nasution (Menteri Pertahanan) dan Jendral Polisi Judo Sutjipto pada 1965
langsung melatih Pemuda Muhammadiyah untuk membentuk Komando Keamanan Muhammadiyah
(KOKAM) dalam rangka menghadapi komunisme. KOKAM tampil secara heroik di bawah propaganda
angkatan darat untuk terlibat dalam penangkapan para aktivis PKI yang nantinya menjadi pembantaian
massal. Seluruh basis massa Muhammadiyah dan AUM-nya dijadikan alat konsolidasi bagi kekuatan anti
komunis. Muhammadiyah selama fase orde lama terlalu banyak mengambil peran politik dibandingkan
peran sosialnya. Aktivisme sosial Muhammadiyah sekedar mempertahankan apa yang sudah ada tanpa
sebuah upaya sistematis.
Upaya Membangun Bersama Negara (Fase Orde Baru)
Jatuhnya Soekarno menandai fase Orde Baru yang sangat pro pada pembangunanisme. Pembangunan
menjadi semboyan utama orde baru untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan stabilitas politik.
Soeharto menjanjikan upaya perbaikan ekonomi yang terpuruk akibat hiperinflasi di akhir masa orde
lama. Orde baru berusaha membangun kembali fondasi ekonomi dengan mengandalkan kebijakan
industrialisasi yang disebut dengan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) yang dijalankan sejak
1969. Industrialisasi yang sangat permisif terhadap modal asing dijadikan fondasi awal bagi bangunan
ekonomi orde baru.
Pada fase pemerintahan Orde Baru negara cenderung mengekspresikan diri sebagai negara kuat atau
strong state, yang memiliki dua ciri yaitu kemampuannya dalam melakukan intervensi kebijakan dan
kedua kemampuan negara dalam melakukan kordinasi terhadap jejaring aktor diluar dirinya dalam
wujud regulasi yang dihormati dan juga kapasitasnya dalam mendorong mobilisasi aktor diluar dirinya.12
Sejak awal kepemimpinannya pemerintah orde baru berusaha serius melakukan upaya pembangunan
sosial yang ditekankan pada tiga aspek, pertama, menekan angka kemiskinan, kedua, menyediakan
fasilitas pelayanan dasar pada sektor pendidikan dan kesehatan, ketiga, memobilisasi potensi
masyarakat untuk terlibat dalam upaya-upaya peningkatan kualitas kesejahteraan. Keefektifan kebijakan
sosialnya dibuktikan dengan penurunan angka kemiskinan secara bertahap. Pada tahun 1970
kemiskinan di Indonesia mencapai angka 60% atau sekitar 70 juta orang berhasil turun secara signifikan
pada periode 1980 hanya tersisa 33.3% atau 42.3 juta orang dan tinggal 15.1 % atau 27,2 juta orang
pada 1990 dan tersisa hanya 11,3 % atau 22,5 juta jiwa penduduk miskin pada era 1996 (fase sebelum
anomali akibat krisis finansial 1996-1998).
Keefektifan negara pada masa Orde Baru juga ditunjukan dengan kemampuannya dalam merespon
tuntutan publik. Pada periode ini publik cenderung menuntut perlunya dua hal, pertama, pemenuhan
kebutuhan dasar berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan dan akses layanan pendidikan
dan kesehatan. Julie Chernov Hwang (2011:99) menyebutkan bahwa Orde Baru memainkan peran
utama dalam penyediaan pendidikan dan kesejahteraan, Rezim itu mengamankan legitimasinya dengan
kemampuannya yang berhasil memastikan stabilitas dan kemakmuran berkelanjutan. Penyediaan
pendidikan dasar universal, swasembada beras, dan pengurangan drastik kemiskinan adalah puncak-
puncak pencapaian era soeharto. Di tingkat lokal, rejim itu memberlakukan serangkaian kebijakan yang
disebut InPres (Instruksi Presiden), yang menyediakan dana untuk memperbaiki infrastruktur dan
bantuan pembangunan bagi pemerintah-pemerintah daerah.
Pada pertengahan 1980-an, negara membangun pusat-pusat kesehatan masyarakat di setiap kecamatan
dan mengaspal jalan yang menghubungkan daerah perdesaan dengan pusat-pusat perkotaan.
Pemerintah berusaha memastikan bahwa semua anak, bahkan mereka yang tinggal di daerah-daerah
terpencil, punya akses pada pendidikan dasar yang murah, dan membangun ribuan sekolah dasar baru
untuk memenuhi permintaan akan pendidikan (Hwang, 2011:99). Mulai akhir 1970-an, Orde Baru
mempercepat pembangunan rumah sakit dan klinik, membangun lebih dari 26.000 pusat kesehatan
masyarakat dan pusat kesehatan masyarakat pembantu (Hwang, 2011:100).
Di balik kapasitas negara dalam memberikan kesejahteraan pada masyarakat, negara cenderung
menampilkan wajah otoritatian dan represif terhadap aktor-aktor yang bersebrangan. Pemerintah Orde
Baru juga mengembangkan paradigma negara integralistik yang menggunakan model korporatokratif.13
Negara menjadi puncak hirarkis kekuasaan dan tidak memberikan ruang di luar strukturnya untuk
berkembang. Seluruh aspirasi masyarakat disalurkan melalui jalur-jalur resmi yang disediakan negara.
12 Dua karakteristik ini ditunjukan secara terpisah dalam dua karya Perter. J Katzeinstein yang pertama dalam
Between Power and Plenty: Foreign Economic Policies in Advanced Industrial States dan yang kedua dalam Small State in World Market: Industrial Policy in Europe lihat dalam Peter A. Gourevich, et, al, 2008, The Political Science of Peter. J. Katzeinstein, American Political Science Association, hal 894-895 13
Negara korporatokrasi yaitu negara yang berusaha menempatkan seluruh dimensi dan kehidupan sosial masyarakat dibawah payung saluran resmi negara guna menjadi mobilisasi legitimasi politik dan sistem rekruitmen elit politik (Nasikun, 2004).
Represi politik juga dilakukan pada seluruh pandangan politik oposisi yang dianggap bertentangan
dengan ajaran resmi negara atau berpotensi melahirkan oposisi. Salah satu bentuk represif tersebut
dengan melarang kemunculan tokoh-tokoh politik islam dalam pentas politik (Remy Mardinier, 2013).
Dalam kondisi seperti ini Muhammadiyah berhasil melepaskan diri dari ruang politis sehingga cukup
diterima sebagai mitra utama negara. Awalnya Muhammadiyah menjadi bagian dari Parmusi tetapi pada
1971 Kongres di Ujung Pandang Muhammadiyah mendeklarasikan diri netral politik dan menjaga
hubungan yang sama dengan semua kekuatan politik (Jurdi (ed), 2010). Netralitas ini cenderung
didukung pemerintah Orde Baru yang sangat berharap akan adanya peran islam sebagai kekuatan moral
spiritual yang berdampingan dengan pembangunan (Hefner, 2000).
Di bawah kepemimpinan AR Fachrudin (1968-1990)14 Muhammadiyah memilih jalur akomodatif,
dialogis, bahkan pak AR dikenal memiliki kedekatan spesial dengan Presiden Soeharto. Sosoknya yang
lugu dan santun serta njawani menjadikan Presiden Soeharto merasa ‘pekewuh’ dengan
Muhammadiyah, Pilihan politik ini membuka hubungan simbiosis mutualisme antara Muhammadiyah
dan Pemerintah terutama dengan dukungan pemerintah terhadap seluruh aktivisme sosial dan
keagamaan Muhammadiyah (Jurdi, 2010:254).15
Pemerintah memandang positif kemampuan Muhammadiyah untuk mendorong lahirnya keswadayaan
dan kolektifisme di masyarakat, khususnya para anggotanya. Negara mendukung sepenuhnya dengan
memberikan bantuan-bantuan melalui pemerintah baik pusat maupun lokal. Situasi ini terjadi
dikarenakan dua faktor. Pertama, anggota-anggota Muhammadiyah sudah banyak yang berada dalam
birokrasi pemerintah di berbagai level. Kedua, Muhammadiyah tetap konsisten untuk tidak terlibat
dalam pergulatan politik secara resmi sehingga mampu menjaga jarak yang cukup aman dengan negara.
Hwang (2011) menyebutkan Abdul Mu’ti mengatakan bahwa Muhammadiyah adalah organisasi
nonpolitis yang berfokus pada layanan-layanan sosial. Soeharto menyukainya selain itu banyak birokrat
dalam pemerintahan adalah mantan anggota atau anggota aktif Muhammadiyah. Karena itulah,
Muhammadiyah bisa bekerja lebih erat dengan pemerintah. Ditambahkan pula oleh Syafi’i Ma’arif,
ketua Muhammadiyah dari 2000 sampai 2004 dalam Hwang (2011) yang mencatat bahwa karena
banyak anggota Muhammadiyah menjadi pegawai negeri, organisasi itu bisa melobi anggota-
anggotanya di departemen-departemen bersangkutan untuk meningkatkan dana-dana pendidikan.
Negara tidak menyimpan kekhawatiran atau rasa curiga dengan tujuan gerakan Muhammadiyah.
Helmke dan Levitsky (2003) menyebutkan jika negara berperan efektif di sisi lain aktor informal memiliki
tujuan yang sama dengan negara maka akan terjadi situasi komplementer atau saling melengkapi antara
negara dan sektor informal. Hwang (2011) menyebutkan dalam menyediakan layanan sosial pemerintah
(orde baru) tidak melakukannya sendirian. Ia berbagi usaha dengan dua organisasi massa Islam: NU dan
14 AR. Fachrudin menolak dijadikan ketua pada 1990, sehingga digantikan KH. Azhar Bashir dan Beliau menduduki
posisi dewan penasehat sampai wafatnya 1995, Kedekatanya dengan Presiden Soeharto ditunjukan dengan pengangkatan dirinya sebagai Dewan Pertimbangan Agung (DPA) periode 1988-1993. Tentang AR, Fachrudin selengkapnya Lihat Suara Muhammadiyah No. 07/80/1995 hal 18-22. 15
Sejak Muktamar 1971 di Ujung Pandang dideklarasikan keputusan Muhammadiyah untuk menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik sebagai sikap netralitas atau high politic Muhammadiyah (lihat Suara Muhamamdiyah, no 13 tahun 85/ Juli 2000, di suplemen jendela persyarikatan hal 6).
Muhammadiyah memainkan peran utama dalam kesejahteraan sosial di desa-desa, kota-kota, dan
lingkungan-lingkungan urban di seluruh Indonesia. NU dan Muhammadiyah hadir dengan kuat dan vital
di tingkat lokal. Baik klinik-klinik NU maupun Muhammadiyah di daerah-daerah perdesaan punya
kapasitas menyediakan layanan kesehatan murah atau gratis kepada orang miskin (Hwang, 2011:101).
Elit-elit Muhammadiyah selalu menggunakan idiom turut berkontribusi dalam proses pembangunan
sebagai bentuk dukungan Muhammadiyah terhadap perspektif pembangunan di masa orde baru.
Hwang (2011) berpendapat bahwa Pemerintah Indonesia mendapatkan legitimasi dari kesanggupannya
memastikan keberhasilan dalam menyediakan pendidikan dan memerangi kemiskinan di tingkat makro.
NU dan Muhammadiyah membantu di tingkat mikro dan lokal. Muhammadiyah memanfaatkan
kedekatannya dengan negara untuk membangun banyak fasilitas pendidikan mulai dari TK hingga
Universitas, Klinik dan Rumah Sakit, Panti Asuhan dan lain-lain yang hampir kesemuanya selalu didukung
oleh aktor-aktor dalam pemerintahan baik di level pusat hingga level daerah, cabang dan ranting.
Sebagaimana dituturkan dr. Nurul Chusna Sekretaris MPKU PWM DIY
“Saat pembangunan rumah sakit Muhammadiyah selalu mengundang para pejabat
pemerintah di berbagai level, termasuk para anggota muhammadiyah yang berada di
pemerintah pusat utamanya menteri untuk membantu menggalang dana pembangunan”.16
Legitimasi dan dukungan dari para elit pemerintahan menjadikan Muhammadiyah terus berkembang
pesat. Di sisi lain, gerakan akar rumput yang digerakan ranting, cabang dan daerah tidak pernah henti
setiap tahun menginisiasi keinginan untuk membangun amal usahanya. Sebagaimana dituturkan
Muhammad Hatta, sekretaris Muhammadiyah PCM Kota Gede
“Kami sejak dulu selalu merencakan setiap tahun perlu membangun apa? setidaknya
merenovasi atau penambahan fasilitas untuk amal usaha, itu hampir semuanya didapat dari
donasi para jamaah Muhammadiyah termasuk mereka yang sejak muda aktifis
Muhammadiyah dan kini sudah sukses dan tersebar dimana-mana”17
Dilihat dari motifnya Muhammadiyah cenderung mempertahankan patronasenya dengan negara dan
menjadi penguat legitimasi negara di masyarakat sebagaimana dikatakan Egbert Harmsen (2008) ketika
negara memberikan peluang bagi civil society, negara cenderung mendapat keuntungan dengan
menjadi puncak dari patronase tersebut sedangkan civil society yang lahir cenderung menjadi salah satu
segmen terbatas dalam pembentukan patronase di masyarakat bertingkat dengan menempatkan
dirinya sebagai representasi masyarakat untuk menjadi segmentasi patronase yang berpuncak kepada
negara. Posisi ini mendatangkan keuntungan bagi Muhammadiyah dengan privilege yang diberikan oleh
negara.
16 Wawancara dengan dr Nurul Chusna, Sekretaris MPKU PWM DIY, pada 17 januari 2014
17 Wawancara dengan Drs. Muhammad Hatta, Sekretaris PCM Kota Gede, pada 16 Januari 2014
Strategi Bertahan di Celah Kekuasaan (Era Reformasi)
Hubungan mesra antara Muhammadiyah dan negara sempat renggang pada pertengahan dekade 90-an,
Muhammadiyah yang dipimpin M. Amien Rais (Ketua PP Muhammadiyah 1994-1998), memulai
dinamika kritisnya terhadap orde baru dengan menyatakan perlunya suksesi kepemimpinan.18 Arus
utama gerakan reformasi berhasil menuntut mundur Presiden Soeharto dari tampuk kepemimpinan
setelah 32 tahun berkuasa. Reformasi yang ditandai dengan pengunduran diri Presiden Soeharto dan
digantikan oleh BJ. Habibie justru memberikan angin segar pada pergerakan islam, mengingat beliau
adalah ketua umum ICMI.
Amien Rais dengan dukungan basis massa Muhammadiyah berhasil membangun sebuah partai reformis
yang diberinama PAN (Partai Amanat Nasional). Kendaraan politik ini mengantarkan beliau menduduki
posisi ketua MPR RI 1999-2004 dan beberapa elit Muhammadiyah diangkat menjadi menteri-menteri
yang memiliki posisi cukup strategis.19 Keberadaan PAN tidak menjadikan Muhammadiyah berpihak atau
menjadi bagian darinya. Muhammadiyah mempertahankan posisi netral dengan menempatkan diri
mengambil jarak yang sama dengan politik. Muhammadiyah mempertahankan sifat politik alokatif atau
memberikan porsi kedekatan yang sama dengan semua kekuatan partai politik. Pilihan ini cenderung
menjadikan Muhammadiyah sebagai aset sosial bagi seluruh kekuatan politik.
Pada kepemimpinan Habibie inilah muncul Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang muncul sebagai
respon atas dua hal, pertama, kebutuhan mendesak mendorong keterlibata masyarakat dalam
mengatasi krisis ekonomi, kedua, tuntutan besar dari komunitas muslim sebagai kekuatan politik yang
cukup besar, terutama mengingat Habibie sendiri sebagai ketua ICMI (Widyawati, 2011). Dinamika
lahirnya UU Zakat sebenarnya muncul sejak pertengahan 90-an dimana Harian Umum Republika (sayap
media ICMI) menelurkan lahirnya Dompet Dhuafa sebagai lembaga amil zakat. Gerakan ini juga direspon
positif oleh berbagai pihak sebgai alternative model dalam trend filantropisme islam di Indonesia yang
dianggap lebih profesional dan transparan. Dompet Dhuafa kemudian menjadi motor gerakan zakat
melalui Forum Zakat (FOZ) yang berhasil menghimpun banyak elemen pengelola zakat baik dari
pemerintah, NGO maupun lembaga zakat karyawan yang berafiliasi dengan perusahaan (Widyawati,
2011). FOZ akhirnya berhasil mengajukan draft RUU Pengelolaan Zakat kepada BJ. Habibie dan diajukan
sebagai inisiatif pemerintah ke DPR yang dalam waktu singkat disahkan menjadi Undang-Undang.
Muhammadiyah terlambat merespon adanya gerakan zakat ini dan masih terus mempertahankan
praktik pengelolaan zakatnya yang konvensional dengan basis dari anggotanya.
18 Sebagian pengamat melihat bahwa fase kritis ini dikarenakan adanya sosok Amien Rais yang muncul sebagai ketua umum pasca muktamar Aceh, 1995 yang tepat beriringan dengan meninggalnya dua pimpinan yang akomodatif yaitu KH. AR. Fachruddin dan KH. Azhar Bashir, dan Muhammadiyah tidak sepenuhnya kritis terhadap pemerintah tokoh muda Muhammadiyah seperti Dien Syamsudin (mantan ketua pemuda Muhammadiyah) saat itu justru mendekat ke orde baru dan berusaha mempertahankan relasi strukturalnya dengan bergabung dengan GOLKAR dan ICMI. Lihat Robert. W. Hefner, 2000, Civil Islam : Muslim and Democratization in Indonesia, Pricenton University Press : UK, hal 149-150 19
Beberapa nama menteri yang anggota aktif Muhammadiyah, Bambang Sudibyo pernah menjabat Menteri Keuangan Kabinet Persatuan Nasional (1999-2000) dan Menteri Pendidikan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu (2004-2009), Malik Fadjar pernah menjabat Menteri Pendidikan Nasional Kabinet Gotong Royong (2001-2004) dan Menteri Agama Kabinet Reformasi Pembangunan (23 Mei 1998-29 Oktober 1999),
Pasca kepemimpinan singkat BJ, Habibie, Amien Rais mampu membangun koalisi poros tengah untuk
mengangkat Abdurahman Wahid –Ketua Umum PB NU- sebagai presiden dengan tetap membawa
beberapa orang Muhammadiyah di kabinet. Begitu juga di masa kepemimpinan Megawati Soekarno
Putri (2001-2004) dan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2013), para elit Muhammadiyah tidak absen
mewarnai kekuasaan baik di eksekutif maupun legislatif melalui berbagai partai politik. Di era reformasi
sifat korporatis negara untuk menguasai aktor-aktor sosial semakin melemah. Di sisi lain telah muncul
pergeseran tuntutan publik yang ingin mendapatkan layanan kesejahteraan yang lebih berkualitas
sementara layanan yang diberikan negara seringkali gagal merespon tuntutan ini akibat keterbatasan
fiskal dan birokrasinya yang tidak responsif sehingga menjadikan negara kurang terlihat semakin kurang
efektif.20 Kondisi demikian tidak mengubah sikap Muhammadiyah yang secara terbuka tetap
memberikan dukungan kepada negara. Negara meresponnya secara positif dengan memberikan porsi
pada kader-kader Muhammadiyah untuk terlibat di pemerintahan. Relasi simbiosis mutualistik ini
menjadikan Muhammadiyah tetap mempertahankan kolaborasinya dengan negara.
Di era keterbukaan pasca reformasi Muhammadiyah dituntut untuk mempertahankan model pelayanan
berbasis amal usahanya. Model layanan berbasis AUM menjadikan peran yang dimainkannya sama
dengan layanan yang direproduksi pemerintah. Posisi ini menjadikan Muhammadiyah tidak bergeser
sebatas melengkapi peran negara. Pilihan tersebut menjadikan nilai kemanfaatan Muhammadiyah
terlokalisir di wilayah basis-basisnya. Sebagaimana dikatakan Said Tuhuleley
“bertahun-tahun Muhammadiyah sibuk membantu negara membangun banyak sekolah,
rumah sakit, panti asuhan dan lain-lain, tapi semuanya harus dihidupi sendiri sehingga
Muhammadiyah disibukan dengan urusan ini, ini menjadikan kita agak terlambat merespon
kebutuhan untuk mengatasi masalah-masalah di lapangan.”21
Kesibukan Muhammadiyah dalam mempertahankan layanan berbasis AUM menjadikannya tejebak pada
rutinitas. Sebagaimana kritik Zuli Qadir (dalam Boy Ztf, Faiq dan Barron (ed), 2008) salah satu aktivis
pemuda Muhammadiyah yang menyebutkan seringkali Muhammadiyah terkesan sibuk dengan urusan
membangun sekolah dan amal usaha tetapi tidak tahu setelahnya untuk apa? Idiomnya yang penting
membangun merawatnya belakangan Ahmad Fuad Fanani (dalam Boy Ztf, Faiq dan Barron (ed), 2008)
juga mengkritisi bahwa kemandegan aktivisme Muhammadiyah yang sekedar pda wilayah rutinitas
merupakan akibat dari kemandegan berfikir dan sekedar mengawetkan warisan masa lalu. Padahal
dalam aktivisme sosial dibutuhkan kerangka berfikir baru agar praktik sosial itu tidak berhenti di tengah
jalan, tidak tepat sasaran dan menjadi sekedar rutinitas. Muhammadiyah terkesan terlambat
merumuskan formulasi aktivisme sosial yang lebih taktis. Keterlambatan ini juga disebabkan karena
rentang organisasi yang panjang dan membuatnya perlu energi ekstra untuk keluar dari zona nyaman,
khususnya dalam pemanfaatan potensi filantropisme di internalnya. dr. Nurul Chusna mengatakan
20 Tentang perubahan tuntutan publik dan responsifitas administratif dan birokrasi negara bisa dilihat dalam Rhee Jeeyang Baum, 2011, Responsive Democracy: Increasing State Accountability in East Asia, USA : The Michigan University Press, hal 4 21 Wawancara dengan Said Tuhuleley, Ketua MPM PP Muhammadiyah pada 16/1/2014
“Muhammadiyah ini institusi besar, bermacam-macam orang disini dan amal usaha sangat
banyak dan kemampuannya tidak seragam sehingga tidak mudah mengubah pola kerja
organisasi ini secara keseluruhan, perlu edukasi dan penyadaran agar tumbuh inisiatif dari
cabang, ranting,”22
Ashad Kusumadjaya, anggota LPCR PP Muhammadiyah, menambahkan,
“Filantropi Muhammadiyah itu sebenarnya besar, di satu cabang Godean saja bisa dapat
sampai angka ratusan juta pertahun –saat ramadahan- itu yang murni dana, belum kalau
dihitung yang lain-lain, di semua amal usaha juga ada penggalangan dana-dana tapi memang
belum terorganisir secara rapi, terutama administrasinya, bayangkan jika semua gerakan di
cabang dan ranting serta amal usaha dihitung, totalnya pasti sangat besar”.23
Meskipun Gerakan Muhammadiyah secara umum terlambat merespon tren gerakan filantropisme baru
tetapi Muhammadiyah di akar rumput telah melahirkan inisiatif mandiri untuk bergerak memberikan
layanan sosial yang tidak bisa disepelekan, di level cabang dan ranting mereka aktif melakukan aktivisme
sosialnya. Muhammadiyah masih memainkan aktivisme sosialnya secara sporadis dengan inisiatif
masing-masing jejaringnya. Sebagaimana yang dikatakan Muhammad Hatta, Sekretaris PCM Kota Gede
“kalau urusan santunan fakir miskin, beasiswa yatim piatu, santunan janda-janda miskin, itu
sudah dilakukan sejak dulu tak pernah berhenti, utamanya oleh ibu-ibu aisiyah di ranting-
ranting, Lazis kita juga diarahkan untuk membantu modal usaha, kemarin kita baru buat outlet
untuk pemasaran produk ibu-ibu rumah tangga, MPM kita juga mulai membina anak-anak
muda, dan juga ibu-ibu untuk berwirausaha”.24
Kehadiran layanan berbasis komunitas di akar rumput memberikan kekuatan bagi Muhammadiyah
dalam memperkuat pengaruh di basis-basisnya sekaligus memberikan kontribusi nyata di tengah
sulitnya situasi ekonomi mengingat saat itu pemerintah sering mengambil kebijakan menaikan harga
BBM. Kebijakan penaikan BBM memang diantisipasi dengan penyelenggaraan jaminan sosial dan
kompensasi yang meliputi: raskin, beasiswa siswa tidak mampu, biaya operasional pendidikan, dll.
Program-program itu belum cukup efektif untuk mengentaskan masyarakat dari masalah kemiskinan
dan kerawanan sosial. Merespon situasi ini Muhammadiyah berusaha menelurkan terobosan baru
terutama dengan munculnya gagasan Neo-PKO yang menjelma menjadi Muhammadiyah Disaster
Manegement Center (MDMC), Lembaga Buruh, Tani dan Nelayan (LBTN) yang berubah menjadi Majelis
Pemberdayaan Masyarakat, Lazis Mu dan juga gerakan Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM)
Lembaga-lembaga ini adalah bentuk kesadaran Muhammadiyah untuk merespon masalah-masalah
sosial aktual. MDMC banyak terlibat intensif dalam proses penanggulangan bencana, sedangkan MPM
berusaha selalu di garis depan dalam memberdayakan petani dan pekerja sektor informal di berbagai
daerah. Gerakan MPM juga direproduksi di berbagai daerah (kota/ kabupaten) dan cabang (kecamatan)
22
Wawancara dengan dr. Nurul Chusna, Sekretaris MPKU PWM DIY pada 17 Januari 2014 23 Obrolan dengan Ashad Kusumadjaya, Anggota LPCR PP Muhammadiyah pada 11 Januari 2014 24
Wawancara dengan Drs. Muhammad Hatta, Sekretaris PCM Kota Gede, pada 16 januari 2014
di berbagai pelosok nusantara. Di sisi lain, Lazis Mu hadir berusaha untuk memberikan wajah baru
pengelolaan zakat yang profesional dengan membangun sinergi jaringan baik di level wilayah, daerah,
cabang hingga amal usaha muhamamdiyah. Adapun BTM berusaha mengakumulasikan kekuatan
ekonomi akar rumput jamaah Muhammadiyah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi akar rumput di
sektor micro finance. Gerakan ini menjadi tren baru yang memiliki pengaruh besar sebagai wujud
komitmen baru muhammadiyah dalam mengatasi masalah-masalah kemiskinan dan kerawanan sosial.
Peran Muhammadiyah dalam mendorong peningkatan kesejahteraan sosial tidak bisa dilepaskan dari
modal yang dimilikinya. Muhammadiyah memiliki tiga modal besar dalam upaya tersebut, pertama, aset
amal usaha yang ribuan dan berbagai macam jenis yang tersebar di seluruh indonesia, kedua,
keberadaan anggota dan jamaahnya serta jejaring organisasi yang tersebar luas di seluruh wilayah
Indonesia, ketiga, keberadaan para elit muhammadiyah yang memiliki posisi strategis baik di dalam
maupun diluar pemerintahan. Ketiga modal itu menjadikan Muhammadiyah secara institusional mampu
memainkan dua peran sekaligus, pertama, melakukan redistribusi sumber daya melalui aktivisme sosial,
kedua, melakukan pressure dan bargaining terhadap negara untuk melakukan perbaikan kualitas
kebijakannya dalam mengatasi masalah sosial. Said Tuhuleley menyampaikan:
“MPM konsen tidak hanya pemberdayaan tapi juga advokasi kebijakan, kami
mendiskusikannya dan melakukan pressure terhadap pemerintah, Pak Dien (Dien Syamsudin,
Ketua Umum PP Muhammadiyah) juga mengambil peran strategis salah satunya dengan
melakukan judicial review undang-undang yang dianggap melanggar konstitusi, kemaren kita
berhasil men-JR UU Migas dan terus bergerak ke sektor-sektor lain khususnya terkait
kebijakan pangan, kami juga buat pillot project sekaligus labolatorium pemberdayaan petani di
Sawangan, Magelang, itu untuk memberi contoh pemerintah bagaimana seharusnya
menangani petani, kami juga terlibat pemberdayaan buruh gendong, abang becak, hingga
komunitas suku pedalaman di sorong”25
Kemampuan memainkan dua peran ini khas dimiliki Muhamamdiyah yang memiliki basis legitimasi dan
pengakuan yang cukup besar dihadapan publik dan negara. Walaupun demikian, Muhammadiyah belum
memiliki sebuah desain sistematis dalam merancang gerakan filantropisnya. Muhammadiyah masih
berusaha memadukan konsolidasi gerakan amal usahanya yang berjumlah ribuan dengan sistem
filantropisnya yang berakar pada komunitas akar rumput di cabang dan ranting. Di sisi lain,
Muhamamdiyah perlu juga mengantisipasi gelagat kebijakan negara dnegan melakukan advokasi
terhadap kebijakan-kebijakan negara.
Penutup
Muhammadiyah merupakan satu contoh dari eksistensi komunitas masyarakat dalam rangka
menciptakan kesejahteraan sosial. Dalam sistem welfare pluralisme kehadiranya sangat membantu
dalam rangka memperkuat modal sosial di masyarakat. Muhammadiyah yang lahir dari dorongan nilai-
nilai ajaran islam mampu mereproduksi sebuah layanan kesejahteraan baik berupa fasilitas dan
pelayanan baik pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial maupun dalam bentuk santuan langsung dan
25 Wawancara dengan Drs. Said Tuhuleley, Ketua MPM PP Muhammadiyah, pada 16 januari 2014
pemberdayaan. Motif awal kelahiran Muhammadiyah muncul sebagai respon aktual atas kondisi sosial
di zamannya dan kemudian berkembang menjadi tradisi dalam lembaga yang terus direproduksi dan
dipertahankan hingga kini sebagai sebuah identitas gerakannya.
Muhammadiyah tumbuh dari sebuah asossiasi sosial keagamaan menjadi sebuah organisasi yang
memiliki jejaring birokratis yang panjang dan memiliki kekuatan sosial dan ekonomi yang menggurita.
Kolektivisme anggotanya yang dibalut dengan identitas religius yang ortodoks melahirkan semangat
pembaharuan yang berurat pada upaya untuk membangun kekuatan praktis organisasinya (otopraksi)
dalam menyediakan layanan pendidikan, kesehatan dan sosial. Kemampuan Muhammadiyah
memberikan layanan menjadikannya meraih legitimasi sebagai patron melalui proses pembentukan
“authority ranking” pada komunitas pribumi.
Muhammadiyah berusaha menarik sumber daya kolektif publik khususnya para anggotanya, sekaligus
berusaha mendekati negara untuk ikut serta mengalokasikan anggarannya untuk memberikan subsidi
dan bantuan hibah yang dilakukan dengan mengandalkan koneksivitas para elitnya yang juga berada di
ruang-ruang birokrasi dan politik. Selain itu Muhammadiyah melalui sayap-sayap geraknya berusaha
pula untuk mengakses dana-dana dari donor-donor internasional untuk mempertahankan aktivisme
sosial utamanya di kawasan bencana.
Motif Layanan Kesejahteraan Muhammadiyah
Institusi Motif Proses
Muhamamdiyah Authority
Ranking
ZISWAF diakumulasikan dari basis solidaritas anggotanya untuk
membangun fasilitas pelayanan, menunjang aktivismenya dan sebagian
distribusi langsung ke fakir miskin
Relasi pelayanan kesejahteraan yang disediakan Muhammadiyah dengan negara cenderung adaptif
dengan celah struktur politik yang dihadapinya. Relasi pelayanan tersebut sangat bergantung pada dua
faktor, yaitu: 1) Kapasitas dan tujuan negara yang dihadapinya dan 2) Pilihan strategi lembaga dalam
menjalankan aktivisme sosial dan pelayanan sosial. Di level elit Muhammadiyah berusaha merespon
insentif yang diberikan negara kepadanya sedangkan di level akar rumput Muhammadiyah cenderung
independen dari pengaruh negara dan lebih mendasarkan pada inisiatif kolektif kader-kadernya.
Relasi Muhammadiyah dengan negara bisa dikategorikan dalam dua fase. Pertama, Fase Kompetisi, dan
Fase Komplementer. Fase Kompetisi diimplementasikan selama era kolonialisme dimana
Muhammadiyah sebagai pengusung aspirasi pribumi menempatkan tujuan yang berbeda dengan negara
kolonial. Negara kolonial membawa misi untuk mempertahankan kolonialisasi, stratifikasi sosial dan juga
upaya pembaratan Hindia sedangkan Muhammadiyah menginginkan kesetaraan kaum pribumi dan
penciptaan masyarakat Hindia yang religius islam (islamisasi). Muhammadiyah menampilkan dua wajah.
Pertama, melakukan usaha kompetisi tertutup dengan pemerintah dalam melakukan layanan
kesejahteraannya, Kedua, melakukan kompetisi terbuka dengan quasy pemerintah “pihak gereja” tanpa
menimbulkan konfrontasi melainkan dengan model peniruan taktis. Sedangkan, Fase Komplementer,
Fase ini berlangsung pasca kemerdekaan, khususnya di era orde baru yang ditandai kesamaan tujuan
Muhamamdiyah dan negara serta efektifitas layanan negara. Muhammadiyah memilih membangun
sinergistas terhadap agenda pembangunan yang diusung negara dengan berusaha menopang negara
melalui reproduksi layanan pendidikan, sosial dan kesehatan. Pilihan ini disambut negara dengan sikap
terbuka dan memberikan dukungan penuh terhadap aktivisme sosial Muhammadiyah. Di era reformasi
kehadiran Muhammadiyah masih berusaha melengkapi kapasitas negara yang belum sepenuhnya
mampu memenuhi pelayanan pendidikan, sosial dan kesehatan. Muhammadiyah berusaha tetap
mempertahankan sifat komplementernya bersamaan dengan upaya untuk membangun sistem
filantropis barunya yang berusaha menjawab inefektivitas layanan yang diberikan negara.
Aktivisme sosial Muhammadiyah dengan segala keterbatasannya telah menjadi pilar penyangga
kesejahteraan khususnya bagi kaum marginal yang belum tersentuh oleh negara. Kekuatan akar rumpur
Muhammadiyah baik kolektif maupun kesadaran individual kadernya menjadi salah satu pilar untuk
merawat solidaritas, kepedulian dan kerelawanan di masyarakat. Kehadiran Filantropisme ternyata tak
sekedar potret kesadaran humanisme dan kepedulian melainkan memiliki pertautan dalam konteks
sosial politik yang berkembang antara masyarakat dan negara, sekaligus menciptakanya sebagai modal
sosial dalam membangun relasi dan pengaruh dengan negara dan masyarakat sekaligus.
Kehadiran Muhammadiyah sebagai volunteer sector memberikan tiga makna pertama, memperkuat
sumber daya yang dimiliki negara di masa krisis maupun di masa perekonomian yang baik dalam rangka
penyelenggaraan layanan sosial, kedua, merawat solidaritas kolektif masyarakat dan menekan
ketergantungan masyarakat pada layanan sosial negara, ketiga, menjadi kekuatan penyeimbang dan
penopang ketika negara dengan sengaja mengabaikan kewajibanya menyediakan layanan kesejahteraan
pada masyarakat seperti di era kolonial. Dengan demikian komitmen Muhammadiyah dalam mendorong
kesejahteraan tidak kontraproduktif dengan tujuan lahirnya negara maupun welfare state. Peran ini jauh
berbeda dengan konsepsi beberapa kelompok islamis baik di dalam maupun di luar negeri yang
memanfaatkan gerakan filantropisme untuk menggerogoti legitimasi negara di tengah negara
mengalami keterbatasan. Secara konsepsional gagasan pelayanan sektor ketiga ala Muhammadiyah
yang bersifat inklusif (bukan untuk kelompoknya saja) bisa direproduksi dan diperkenalkan sebagai
buffer system untuk menopang welfare state yang tengah mengalami keterbatasan di tengah
perekonomian dunia yang sedang tidak terlalu kondusif atau mengalami stagnasi berkepanjangan. Di sisi
lain Muhammadiyah harus berani terus menginstropeksi diri untuk memperbaiki sistem
filantropismenya untuk memberikan kekuatan layanan kesejahteraan yang lebih efektif dan tetap dapat
diakses kelompok-kelompok paling marginal.
Daftar Pustaka:
Alfian, 2012, Politik Kaum Modernis : Perlawanan Muhammadiyah terhadap Kolonialisme Belanda,
Jakarta: Al Wasat
Al Makassary, Ridwan, 2006, Pengarus Utamaan Filantropi Islam untuk Keadilan Sosial di Indonesia:
Proyek yang Belum Selesai, Jurnal Galang, Volume. 1 No. 3, April 2006
Baum, Rhee Jeeyang, 2011, Responsive Democracy: Increasing State Accountability in East Asia, USA :
The Michigan University Press
Beik, Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyianti, 2013. Optimization of Zakat Instrument in Indonesia’s Poverty
AlleviationProgram, diakses melaluihttp://www.seadiproject.com/0_repository/-
Session%203C%20-%20-Irfan%20Syauqi%20Beik(1).pdf pada 20 November 2013
Boy Ztf, Pradana, M. Hilmi Faiq dan Zulfan Barron (ed), 2008, Era Baru Gerakan Muhammadiyah,
Malang: UMM Press
Darban, Ahmad Adaby, 2000, Sejarah Kauman: Menguak Identitas Kampung Muhammadiyah,
Yogyakarta: UGM Press
Dixon, John dan Robert P. Scheurrel (ed.), 1995. Social Welfare in Indigenous People, London : Routledge
Fauzia, Amelia, 2013, Faith and State : A history Islamic Philanthropy in Indonesia, Leiden:Brill
Gourevich, Peter A, et, al, 2008, The Political Science of Peter. J. Katzeinstein, American Political Science
Association
Harmsen, Egbert, 2008, Islam, Civil Society and Social Work :Muslim Voluntary Welfare Association in
Jordan between Patronage and Empowerment, Leiden : Amsterdam University Press
Hefner, Robert. W, 2000, Civil Islam : Muslim and Democratization in Indonesia, Pricenton University
Press : UK
Helmke, Gretchen, dan Steven Levitsky, 2003. Informal Institution and Comparative Politics : A Research
Agenda, Kellog Institute : Working Paper #307- September 2003
Heriej, Erieck, Ucu Martanto dan Ahmad Musyadad (ed), 2004, Politik Transisi Pasca Soeharto,
Yogyakarta :FISIPOL UGM
Hunsaker, J dan B, Hanzl, Memehami Filantropi Keadilan Sosial, Jurnal Galang, vol. 1 no. 1, Oktober 2003
Hwang , Julie Chernov, 2011, Umat Bergerak : Mobilisasi Damai Kaum Islamis di Indonesia, Malaysia dan
Turkti, Jakarta: Freedom Institute
Ife, Jim, dan Frank Tesoriero, 2008, Community Development : Alternatif Pengembangan Masyarakat di
Era Global, Pustaka Pelajar: Yogyakarta
Jahar, Asep Saepudin, 2010, Masa Depan Filantropi Islam di Indonesia: Kajian Lembaga-Lembaga Zakat
dan Wakaf, Annual Conference in Islamic Studies (ACIS) ke 10, Banjarmasin, 1-4 November
Jurdi, Syarifudin, 2010, Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006, Yogyakarta :
Pustaka Pelajar
Jurdi, Syarifudin (ed), 2010, Satu Abad Muhamamdiyah : Gagasan Pembaharuan Sosial Agama, Jakarta:
Kompas
Kozlowski, Gregory C. Otoritas Agama, Reformasi dan Filantropi di Dunia Islam Kontemporer, dalam
Ilchman, E Warren, et, al, 2006. Filantropi di Berbagai Tradisi Dunia, Jakarta: Center of the
Study of Religion and Culture, UIN Syarif Hidayatullah
Komter, Aafke A, 2005, Social Solidarity and the Gift, Cambridge : Cambridge University Press
Kurasawa, Aiko, 1993, Mobilisasi dan Kontrol : Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-
1945. Jakarta: Grasindo
Latief, Hilman, 2010. Melayani Umat :Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis,
Jakarta : Maarif Institut dan Kompas Gramedia
-------------------, 2013. Politik Filantropi Islam di Indonesia: Negara, Pasar dan Masyarakat Sipil,
Yogyakarta: Ombak
-------------------, 2012, Islamic Charities and Social Activism: Welfare Dakwah and Politics in Indonesia,
diakses melalui http://www.hilmanlatief.net/2012/09/islamic-charities-and-social-activism-
.html
Latif, Yudi, 2005, Intelegensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Intelegensia Muslim Abad 20, Mizan:
Bandung
Lucas, Anton E, 2004, One Soul One Struggle : Peristiwa Tiga Daerah, Yogyakarta: Resist Book
Ma’arif, Syafi’i. 2012, Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita, Jakarta: Democracy Project :
Yayasan Abad Demokrasi
Madinier, Remy, 2013, Partai Masyumi : Antara Godaan Demokratis dan Islam Integral, Bandung:Mizan
Mc Chesney, Robert D. Charity and Philanthropy in Islam, diakses melalui
http://www.learningtogive.org/faithgroups/phil_in_america/philanthropy_islam.asp pada 20
november 2013
Midgley, James, 1997. Social Welfare in Global Context, London : Sage Publication
Mitsuo, Nakamura, 1983, Bulan Sabit Muncul Dibalik Beringin : Studi tentang Pergerakan
Muhammadiyah di Kota Gede, Yogyakarta : Gajah Mada University Press
Noer, Deliar, 1982. Gerakan Islam Modern di Indonesia : 1990-1942, Jakarta: LP3ES
Pestoff, Victor A, 2009. A Democratic Architecture for the Welfare State, New York : Routledge
Payton, Robert, 1988. Philanthropy: Voluntary Action for The Public Good, New York: American Council
on Education, Macmillan
Shihab, Alwi, 1997, Membendung Arus : Respon Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi
Kristen di Indonesia, Bandung : Mizan
Vandendael, Anoux, et al, 2013, Stimulating Civil Society The Perspective of INGO: an Explorative Study
of Indonesia, Erasmus University
Widyawati, 2011. Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca Orde Baru: Studi tentang Undang-
Undang Zakat dan Undang-Undang Wakaf, Jakarta: Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif
Hidayatullah
Sumber lain :
Al Quran
Suara Muhammadiyah. No. 17 Tahun 80/ September 1995
Suara Muhammadiyah No. 07 Tahun 80/ April 1995.
Suara Muhamamdiyah. No. 13 Tahun 85/ Juli 2000
Wawancara : Wawancara dengan dr Nurul Chusna, Sekretaris MPKU PWM DIY, pada 17 januari 2014 Wawancara dengan Drs. Muhammad Hatta, Sekretaris PCM Kota Gede, pada 16 Januari 2014 Wawancara dengan Said Tuhuleley, Ketua MPM PP Muhammadiyah pada 16 Januari 2014
Obrolan dengan Ashad Kusumadjaya, Anggota LPCR PP Muhammadiyah pada 11 Januari 2014