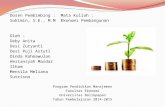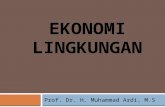BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pemberdayaan Ekonomi ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pemberdayaan Ekonomi ...
8
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
Pemberdayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai kata
nomina (kata benda) yang berarti proses, cara, perbuatan,
memberdayakan(Departemen Pendidikan Nasional, 2008; 300). Pemberdayaan
dalam bahasa Inggris disebut sebagai empowerment. Istilah pemberdayaan
diartikan sebagai upaya mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki
masyarakat agar menjadi sebuah sistem yang bisa mengorganisasi diri mereka
sendiri secara mandiri. Individu bukan sebagai obyek, melainkan sebagai
pelaku yang mampu mengarahkan diri mereka sendiri kearah yang lebih baik.
Menurut Ginandjar Kartasasmita (1996:249), pemberdayaan ekonomi
rakyat adalah “Upaya yang merupakan pengerahan sumber daya untuk
mengembangkan potensi ekonomi rakyat untuk meningkatkan produktivitas
rakyat sehingga, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di
sekitar keberadaan rakyat, dapat ditingkatkan produktivitasnya”.
Dalam situs yang ditulis oleh Daniel Sukalele (wordpres.com diakses
tgl. 25 Juni 2015) pemberdayaan dimaksudkan bahwa:
a. Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan
mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang
dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.
b. Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara
produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi
danpendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk
menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap
empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi,
akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan.
9
Menurut Kindervater dalam Kusnadi, dkk (2005: 220), pemberdayaan
adalah proses peningkatan kemampuan seseorang baik dalam arti pengetahuan,
keterampilan, maupun sikap agar dapat memahami dan mengontrol kekuatan
sosial, ekonomi, dan atau politik sehingga dapat memperbaiki kedudukannya
dalam masyarakat. Sedangkan dalam bukunya Edi Suharto (2005: 58),
pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat
untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi
terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi
kehidupannya. Pemberdayaan ini menekankan bahwa orang memperoleh
keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi
kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.
Dalam kutipannya Djohani dalam Kusnadi, dkk (2005: 220),
menyebutkan pemberdayaan masyarakat dimaksudkan mengembangkan
kemampuan masyarakat agar secara berdiri sendiri memiliki keterampilan
untuk mengatasi masalah-masalah mereka sendiri. Permasalah yang timbul
dalam masyarakat bisa berwujud persoalan ekonomi, pendidikan, sosial dan
lainnya.
Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk menciptakan atau
meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun
berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan
kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya, (Direktorat Jendral
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2009: 126). Untuk mengembangkan
pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka perlu dilakukan penguatan
pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan
pemasaran.
Dalam konteks ini pemberdayaan ekonomi untuk penguatan masyarakat
dalam mendapatkan gaji/upah yang memadai, untuk memperoleh informasi,
pengetahuan dan ketrampilan, sehingga memperoleh peningkatan hasil secara
ekonomi. Permberdayaan di bidang ekonomi merupakan upaya untuk
membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan
membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta
10
berupaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat adalah unsur
dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan. Dalam pengertian yang
dinamis, yaitu mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan
masyarakat menjadi sumber dari apa yang dikenal sebagai Ketahanan Nasional
(Mubyarto, 2000: 263-264).
Dalam kaitan pemberdayaan ekonomi masyarakat berarti segala
kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
(basic need) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.
Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang digunakan untuk memenuhi
kebutuhan pendidikan anggota keluarga merupakan bentuk potensi masyarakat
yang digunakan untuk berpartisipasi pada pendidikan.
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, pemberdayaan ekonomi
masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan
penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk
mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk
memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan untuk meningkatkan
kemampuan masyarakat agar mampu berdiri sendiri untuk mengatasi masalah-
masalah mereka sendiri, meningkatkan kualitas hidup, mencapai kesejahteraan
dan memperbaiki kedudukannya dalam masyarakat.
2. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Dalam pemberdayaan ada kondisi dimana masyarakat secara umum
memiliki kesamaan hak dan kewajiban yang terwujud dalam kesempatan,
kedudukan, peranan yang dilandasi sikap dan perilaku saling membantu dalam
seluruh aspek kehidupan masyarakat. Upaya pemberdayaan membutuhkan
dukungan dari berbagi pihak, baik pemerintah maupun lembaga swadaya
masyarakat. Pemberdayaan yang dilakukan memiliki dampak keberdayaan
masyarakat untuk keluar dari hambatan struktural, sehingga masyarakat yang
berdaya ini nantinya dapat mengaktualisasikan potensi diri dan kapasitasnya
untuk menghadapi tantangan eksternal sebagai dampak dari pembagunan.
11
Menurut Agnes Sunartiningsih (2004: 140), menyebutkan proses
pemberdayaan masyarakat yang dilakukan diharapkan mampu:
1. Menganalisis situasi yang ada dilingkungannya.
2. Meningkatkan kualitas hidup anggota
3. Mencari pemecahan masalah berdasarkan kemampuan dan keterbatasan
4. yang mereka miliki.
5. Meningkatkan penghasilan dan perbaikan penghidupan di masyarakat.
6. Mengembangkan sistem untuk mengakses sumber daya yang diperlukan.
Gambaran tentang tujuan dari pemberdayaan masyarakat tersebut
menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan
sosial, yaitu meningkatkan masyarakat yang tidak berdaya menjadi berdaya
dan memperkuat kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi,
maupun sosial seperti mempunyai kepercayaan diri, mampu menyampaikan
aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial,
dan mandiri dalam melaksanakan tugas kehidupannya (Edi Suharto, 2005: 60).
Berdasarkan beberapa kutipan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa
tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu agar masyarakat berdaya dan
mempunyai pengetahuan serta keterampilan yang digunakan dalam kehidupan
untuk meningkatkan pendapatan, memecahkan permasalahan yang dihadapi,
dan mengembangkan sistem untuk mengakses sumber daya yang diperlukan.
3. Pendekatan dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat
terutama mereka yang miskin sumberdaya, kaum perempuan dan kelompok
lain yang terabaikan lainnya didukung agar mampu meningkatkan
kesejahteraannya secara mandiri. Dalam proses ini, lembaga berperan sebagai
fasilitator. Edi Suharto (2005: 67), mengatakan pelaksanaan proses dan
pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat dicapai melalui penerapan
pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat dengan 5P yaitu Pemungkinan,
Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan.
12
1. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan
potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus
mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural
yang menghambat.
2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki
masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-
kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan
segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang
kemandirian mereka.
3. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok
lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya
persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan
lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap
kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala
jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat
mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya.
Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke
dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi
keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam
masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan
kesimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan
berusaha.
Sedangkan menurut Noeng Muhadjir dalam Yoyon Suryono (2008: 17),
menyebutkan bahwa, dalam menempatkan kualitas manusia sebagai objek
pengembangan sumber daya manusia dengan dua indikator, yaitu indikator
instrumental dan indikator substansial. Indikator instrumental meliputi
kreativitas, kebebasan, tanggung jawab dan kemampuan produktif. Indikator
substansial meliputi aspek sosial, politik, agama, ekonomi, budaya, ilmu dan
fisik.
13
Keduanya dapat digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan kualitas
manusia. Secara substansial, keberhasilan pengembangan kualitas manusia
ditunjukkan dalam bentuk pendapatan, pendidikan, kesehatan, keimanan,
ketangguhan fisik, ketangguhan mental, dan seni.
Pemberdayaan dalam ekonomi terbentuk sebagai antitesis terhadap
model pembangunandan model industrialisasi yang kurang memihak pada
rakyat mayoritas. Pada konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai
berikut:
1. Bahwa proses pemusatan kekuasan terbangun dari pemusatan penguasaan
faktor produksi.
2. Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja
dan masyarakat yang pengusaha pinggiran.
3. Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan,
sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk
memperkuat dan legitimasi.
4. Kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi,
secara sistematik akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu
masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya. Akhirnya yang terjadi adalah
dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai.
Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan
pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai.
Oleh karena itu, tujuan akhir pemberdayaan masyarakat dalam bidang
ekonomi adalah meningkatnya pendapatan masyarakat lemah. Pendapatan
masyarakat pada umumnya berasal dari upah/gaji dan dari surplus usaha. Pada
umumnya masyarakat yang tunadaya (tidak berkemampuan) secara ekonomi
hanya menerima upah/gaji rendah. Rendahnya gaji/upah yang diterima
masyarakat tunadaya ini disebabkan karena mereka pada umumnya memiliki
ketrampilan yang terbatas.
14
4. Pola-pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan
yang tepat sasaran sangat diperlukan. Bentuk yang tepat sasaran dalam
pemberdayaan adalah dengan memberikan kesempatan kepada kelompok
miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang
telah mereka tentukan. Beberapa bentuk praktik pemberdayaan ekonomi
masyarakat yaitu:
1. Bantuan Modal.
Salah satu aspek permasalahan yang dihadapi masyarakat tuna daya adalah
permodalan. Lambannya akumulasi kapital di kalangan pengusaha mikro,
kecil, dan menengah, merupakan salah satu penyebab lambannya laju
perkembangan usaha dan rendahnya surplus usaha di sektor usaha mikro, kecil
dan menengah. usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi melalui
aspek permodalan ini adalah 1) pemberian bantuan modal ini tidak
menimbulkan ketergantungan masyarakat; (2) pemecahan aspek modal ini
dilakukan melalui penciptaan sistem yang kondusif baru usaha mikro, usaha
kecil, dan usaha menengah untuk mendapatkan akses di lembaga keuangan.
2. Bantuan Pembangunan Prasarana.
Usaha mendorong produktivitas dan tumbuhnya usaha, tidak akan memiliki arti
penting bagi masyarakat, kalau hasil produksinya tidak dapat dipasarkan, atau
dapat dijual hanya dengan harga yang sangat rendah. Oleh sebab, itu
komponen penting dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi
adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran.
Tersedianya prasarana pemasaran dan atau transportasi dari lokasi produksi ke
pasar, akan mengurangi rantai pemasaran dan pada akhirnya akan
meningkatkan penerimaan petani dan pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan
pengusaha menengah. Artinya, dari sisi pemberdayaan ekonomi, maka proyek
pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal, memang strategis.
15
3. Bantuan Pendampingan.
Pendampingan masyarakat tunadaya memang perlu dan penting. Tugas utama
pendampingan ini adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi
mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil,
maupun usaha menengah dengan usaha besar.
4. Penguatan Kelembagaan
Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat lemah, pada mulanya dilakukan
melalui pendekatan individual.
Pendekatan individual ini tidak memberikan hasil yang memuaskan. Oleh
sebab itu pendekatan yang dilakukan sebaiknya dengan pendekatan kelompok.
Alasannya adalah, akumulasi kapital akan sulit dicapai di kalangan orang
miskin, oleh sebab itu akumulasi kapital harus dilakukan bersama-sama dalam
wadah kelompok atau usaha bersama. Demikian pula dengan masalah
distribusi, orang miskin mustahil dapat mengendalikan distribusi hasil produksi
dan input produksi, secara individual. Melalui kelompok, mereka dapat
membangun kekuatan untuk ikut menentukan distribusi.
5. Penguatan Kemitraan usaha.
Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah penguatan bersama,
dimana yang besar hanya akan berkembang kalau ada yang kecil dan
menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau ada yang besar dan
menengah. Daya saing yang tinggi hanya ada jika ada keterkaitan antara yang
besar dengan yang menengah dan kecil. Sebab hanya dengan keterkaitan
produksi yang adil, efisiensi akan terbangun. Oleh sebab itu, melalui kemitraan
dalam bidang permodalan, kemitraan dalam proses produksi, kemitraan dalam
distribusi, masing-masing pihak akan diberdayakan.
Dalam kutipan lain bahwa ada 4 (empat) konsep pemberdayaan
ekonomi menurut Sumodiningrat (1999) seperti yang dikutip oleh Mardi
Yatmo Hutomo (2000: 6), secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:
1. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh
rakyat.
16
Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah perekonomian
nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas
untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri.
2. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi
yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme
pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah
kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan
melalui perubahan struktural.
3. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi
tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari
ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian.
Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi: a) pengalokasian
sumber pemberdayaan sumberdaya; b) penguatan kelembagaan; c)
penguasaan teknologi; dan d) pemberdayaan sumberdaya manusia.
4. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan
produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya
memberikan suntikan modal sebagai stumulan, tetapi harus dijamin
adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan
yang masih lemah dan belum berkembang.
5. Kebijakannya dalam pembedayaan ekonomi rakyat adalah: a) pemberian
peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya
modal); b) memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi
rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar price taker;
c) pelayanan pendidikan dan kesehatan; d) penguatan industri kecil;
e) mendorong munculnya wirausaha baru; dan f) pemerataan spasial.
6. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: a) peningkatan akses
bantuan modal usaha; b) peningkatan akses pengembangan SDM; dan
c) peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung
sosial ekonomi masyarakat lokal.
17
Dari uraian tersebut, menurut hemat penulis bahwa pemberdayaan
ekonomi masyarakat yang terjadi secara individu perlu didukung oleh
Pemerintah setempat baik secara kebijakan maupun dukungan bantuan untuk
memudahkan pengembangan usaha masyarakat secara berkelanjutan. Selain
itu, bentuk dukungan Pemerintah lainnya bisa dalam bentuk peningkatan
pemahaman masyarakat miskin tentang pengembangan usaha melalui bantuan
kredit atau bentuk pendampingan dalam peningkatan keterampilan masyarakat.
B. Kajian tentang Pemberdayaan Eknomi Masyarakat Desa.
1. Pengertian Masyarakat
Konsep tentang masyarakat dipahami seperti: masyarakat desa,
masyarakat kota, masyarakat Betawi, masyarakat Jawa, dll. Meskipun secara
mudah bisa diartikan bahwa masyarakat itu berarti warga namun pada dasarnya
konsep masyarakat itu sendiri sangatlah abstrak dan sulit ditangkap.
Secara bahasa, kata ’’masyarakat’’berasal dari bahasa Arab ’’syarikat’’
yaitu pembentukan suatu kelompok atau golongan atau kumpulan. Dalam
bahasa Inggris, pergaulan hidup disebut ’’social’’ (sosial), hal ini ditujukan
dalam pergaulan hidup kelompok manusia terutama dalam kelompok
kehidupan masyarakat teratur.
Secara umum, masyarakat adalah sekelompok orang/ manusia yang
hidup bersama yang mempunyai tempat/ daerah tertentu untuk jangka waktu
yang lama dimana masing-masing anggotanya saling berinteraksi.Interaksi
yang dimaksudkan berkaitan dengan sikap, tingkah laku dan perbuatan.Segala
tingkah laku dan perbuatan tersebut diatur dalam suatu tata tertib/ undang-
undang/ peraturan tertentu yang disebut hukum adat. (Abdullah Idi, 2001: 38).
Dalam suatu masyarakat berupa kelompok-kelompok manusia yang terkait
oleh sistem-sistem, adat istiadat, ritus-ritus serta hukum-hukum khas, dan yang
hidup bersama-sama dalam wilayah tertentu, iklim dan bahan makanan yang
sama.
18
Selanjutnya Soerjono Soekanto (2012; 132), menjelaskan tentang istilah
community dapat diterjemahkan sebagai “masyarakat setempat” yang
menunjukkan pada warga sebuah desa, kota, suku atau bangsa. Anggota
masyarakat dalam suatu kelompok, baik kelompok itu besar maupun kecil ,
hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut
dapat memenuhi kepentinga-kepentingan hidup yang utama. Kelompok atau
kumpulan anggota masyarakat tersebut disebut dengan istilah masyarakat
setempat.
Dengan paparan tersebut tentang masyarakat dapat kami simpulkan
bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama tinggal
di suatu tempat atau didaerah tertentu dengan mempunyai aturan tertentu
tentang tata cara hidup mereka menuju satu tujuan yang sama dengan
menghasilkan sebuah kebudayaan, dengan indikasi: 1) Adanya sekelompok
manusia, 2) Adanya peraturan atau undang-undang yang mengatur mereka. 3)
Bertempat tinggal didaerah tertentu dan telah berjalan cukup lama, dan 4)
Adanya kebudayaan atau adat istiadat setempat.
Menurut Kingley Davis dalam bukunya Soerjono Soekanto (2012: 135)
bahwa dalam mengadakan klasifikasi masyarakat setempat, dapat digunakan
empat kriteria yang saling berpautan yaitu:
1. Jumlah penduduk
2. Luas, Kekayaan dan kepadatan penduduk daerah
3. fungsi-fungsi khusus masyarakat setempat terhadap seluruh masyarakat
4. organisasi masyarakat setempat yang bersangkutan.
Kriteria ini digunakan untuk membedakan antara bermacam-macam jenis
masyarakat setempat yang sederhana dan modern serta antara masyarakat
pedesaan dan perkotaan. Masyarakat sederhana dengan indikasi organisasinya
sederhana, penduduknya tersebar, perkembangan teknologi lambat, sosialisasi
individu lebih mudah karena hubungan yang erat antar warga masyarakat
setempat yang masih sederhana, kesetiaan dan pengabdian terhadap kelompok
sangat kuat.
19
Dalam masyarakat modern, membedakan antara masyarakat pedesaan
dengan masyarakat perkotaan. Pada masyarakat sederhana atau bersahaja
pengaruh dari kota secara relative tidak ada. Pada konsep masyarakat desa
sudah menerima pengaruh dari perkembangan kota-kota yang ada
disekitarnya.Warga pedesaan umumnya mempunyai hubungan yang erat
dengan sistem kehidupan berkelompok atas dasar kekeluargaan. Penduduk
masyarakat desa pada umumnya hidup dari pertanian, sekalipun ada pekerjaan-
pekerjaan lainnya sebagai pekerjaan sambilan seperti: tukang genteng atau
bata, membuat gula dan lainnya. Pekerjaan sampingan ini dilakukan pada saat
masyarakat menunggu masa panen tiba atau masa menanam padi. Sebagai
petani masyarakat desa tersebut memiliki tanah garapan yang cukup ataupun
hanya sebagai buruh tadi yang pekerjaan intinya adalah pertanian.
Dalam masyarakat desa, golongan orang tua umumnya memegang
peranan penting. Hubungan antara pemerintah dengan masyarakat lebih
bersifat informal. Masyarakat desa dalam aaktivitas ekonomi biasanya lebih
digunakan untuk keperluaan kehidupan. Masyarakat desa umumnya juga
dengan kehidupan keagamaan yang lebih kental dan kuat. Sementara itu, pada
batas wilayah desa dengan kota terjadi banyak urbanisasi ke kota karena ada
faktor yang menarik dari kota seperti peningkatan ekonomi, hiburan, fasilitas
sosial yang mudah digunakan dan lainnya.
2. Hakikat Pemerintahan Desa
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa,
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan asal- usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam Pasal 1 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 12 Tahun
2007, tentang pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan
Kelurahan, yang disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
20
memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Republik Indonesia.
Pengertian desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan
sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu dan antar mereka saling
mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan
banyak bergantung secara langsung dengan alam. Oleh karena itu, desa
diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sektor
agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat, bersahaja, serta
tingkat pendidikan yang rendah (Juliantara, 2005: 18).
Dengan beberapa rujukan tentang desa, maka indikasi desa adanya
bentuk kesatuan dalam masyarakat yang mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakatnya sendiri.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat desa
Pemberdayaan adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan
kapasitas masyarakat. Dalam konsep ini berarti masyarakat turut aktif
berpartisipas dan terlibat dalam kegiatan tersebut.Menurut Ach. Wazir Ws., et
al. (1999: 29) partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara
sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu,
seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam
kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai,
tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama.
Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan
masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di
masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi
untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan
keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.
21
Mikkelsen (1999: 64) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu:
1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa
ikut serta dalam pengambilan keputusan;
2. Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk
meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi
proyek-proyek pembangunan;
3. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan
yang ditentukannya sendiri.
4. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa
orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan
kebebasannya untuk melakukan hal itu;
5. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan
para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar
supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-
dampak sosial;
6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri,
kehidupan, dan lingkungan mereka.
Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan ekonomi di lingkungan
setempat berarti bentuk partisipasi yang nyata dari masyarakat terlibat dalam
kegiatan ekonomi, baik secara individu maupun kelompok yang bertujuan
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara bersama.
4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Mendukung Pendidikan
Formal.
Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan
yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (UU No.20 Tahun
2003). Satuan pendidikan di Indonesia terdapat tiga kelompok, yaitu jalur
pendidikan informal, pendidikan formal dan pendidikan non formal.
22
Pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga
tanggung jawab orang tua dan masyarakat. Dalam Undang- undang Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I pasal 1 dinyatakan
bahwa : “Pendukung dan penunjang pelaksanaan pendidikan yang terwujud
sebagai tenaga, sarana, dan prasarana yang tersedia dan didayagunakan oleh
keluarga, masyarakat, peserta didik dan pemerintah, baik sendiri-sendiri
maupun bersama-sama”. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa peran serta
masyarakat dan orang tua bertujuan mendayagunakan kemampuan yang ada
pada orang tua dan masyarakat bagi pendidikan untuk mewujudkan tujuan
pendidikan, terlebih pada era otonomi sekolah (Manajemen Berbasis Sekolah)
saat ini peran serta orang tua dan masyarakat sangat menentukan.
Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal hidup dari masyarakat,
oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Sekolah jelas bukan sekolah yang
berjalan terisolasi dari masyarakat, melainkan sekolah yang berorientasi
kepada kenyataan-kenyataan kehidupan dan hidup bersama-sama
masyarakatnya. Masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat
didayagunakan dalam mendukung program-program sekolah. Untuk itu agar
sekolah dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, maka program sekolah
harus sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
Pembangunan masyarakat merupakan proses dinamisasi, demokrasi,
dan modernisasi. Ketiga proses tersebut adalah gerakan membangkitkan
kesadaran masyarakat untuk memajukan kualitas kehidupannya dengan
mengutamakan pada potensi-potensi yang ada serta menekankan keguyuban
masyarakat dalam berprakarsa dan melaksanakan program-program
pembangunan masyarakat.
Sudjana (2004: 271), menyebutkan tahapan-tahapan untuk mencapai
tujuan yang telah dirumuskan dalam pembangunan masyarakat meliputi:
1. Masyarakat melakukan identifikasi kebutuhan atau keinginan yang mereka
rasakan, serta sumber-sumber dan kemungkinan hambatan untuk memenuhi
kebutuhan itu.
23
2. Mendiskusikan tujuan yang ingin dicapai serta berbagai program atau
kegiatan yang mungkin dilaksanakan dalam mencapai tujuan.
3. Mendiskusikan rancangan program yang diprioritaskan. Komponen-
komponen seperti sumber daya manusia, fasilitas, biaya, proses dan
kemungkinan bantuan dari luar yang ditetapkan melalui musyawarah.
Partisipasi masyarakat di sekitarnya keberadaan sekolah dimana
pendidikan formal dilaksanakan menjadi sangat penting. Di satu sisi sekolah
memerlukan masukan dari masyarakat dalam menyusun program yang relevan,
sekaligus memerlukan dukungan masyarakat dalam melaksanakan program
tersebut. Dilain pihak, masyarakat memerlukan jasa sekolah untuk
mendapatkan program-program pendidikan sesuai dengan yang diinginkan.
Jalinan semacam itu dapat terjadi, jika masyarakat dapat saling melengkapi
untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah.
Partisipasi masyarakat hendaknya menjadi pendorong dapat terwujud
dan terpelihara keberadaan dan pengembangan sekolah. Pada akhirnya apabila
partisipasi telah terpelihara dengan baik, maka sekolah tidak akan mengalami
kesulitan yang berarti dalam mengembangkan berbagai jenis program, karena
semua pihak telah memahami dan merasa bertanggung jawab terhadap
keberhasilan suatu program yang akan dikembangkan oleh pihak sekolah.
Dengan sendirinya agar semua terpelihara dengan baik, maka harus ada
komunikasi timbal balik antara sekolah dengan semua pihak yang
berkepentingan, terutama masyarakat setempat. Dengan demikian hubungan
interaksi yang terbangun antara sekolah dengan masyarakatmerupakan satu
kesatuan yang utuh dalam menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu
di sekolah.
Melalui upaya-upaya yang dilakukan pihak sekolah diharapkan
masyarakat dan orang tua murid dapat berpartisipasi aktif dan optimal dalam
proses pendidikan di sekolah. Hal ini berarti bahwa pemberdayaan masyarakat
harus menjadi tujuan utama dan peran serta masyarakat bukan hanya pada
stakeholders, tetapi menjadi bagian mutlak dari sistem pengelolaan.
24
Hal ini jelas menggambarkan bahwa sekolah dalam menyelenggarakan
pendidikan hendaknya melibatkan masyarakat.
Dengan adanya bantuan ataupun kerjasama-kerjasama tersebut
diharapkan penyelenggaraan pendidikan menjadi besar. Ketika partisipasi dari
masyarakat semakin besar maka secara otomatis makin besar pula rasa
memiliki masyarakat terhadap lembaga pendidikan tersebut. Adanya rasa
memiliki masyarakat terhadap lembaga pendidikan merupakan ditunjukkan
dalam beberapa tindakan masyarakat dalam pengembangan pendidikan di
sekolah. Beberapa dukungan yang dapat diberikan masyarakat terhadap
kegiatan pendidikan antara lain: memantau pelaksanaan pendidikan,
memberikan masukan dan bahkan menjaga keberlangsungan pendidikan, turut
mendukung kebijakan pemerintah tentang partisipasi pendidikan, dan lainnya.
Dukungan masyarakat dalam pendidikan formal yang nyata bisa
dijelaskan dengan meningkatnya partisipasi masyarakat melalui orang tua
siswa yang mau menyekolahkan putra-putrinya. Kemauan orang tua siswa
dalam menyekolahkan anak-anak mereka merupakan dukugan awal
masyarakat terhadap keberadaan sekolah. Hal ini, terhadap pembiayaan
pendidikan yang sebagian besar ditanggung orang tua siswa, mampu didukung
oleh orang tua dan masyarakat setempat disamping bantuan Pemerintah.
Dukungan masyarakat terhadap pendidikan formal tercipta melalui orang tua
yang berpartisipasi menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah dan jenjang
pendidikan formal yang makin baik. Kesadaran orang tua akan pentingnya
sekolah bagi anak-anaknya menjadi pertimbangan dan semangat orang tua
untuk mengembangkan kegiatan usaha yang makin baik, sehingga menjadi
sumber utama menyekolahkan anak-anaknya dari kegiatan ekonomi yang ada
di masyarakat.
25
C. Kajian tentang Objek Wisata untuk Pemberdayaan Ekonomi
1. Definisi Pariwisata
Istilah pariwisata berasal dari Bahasa Sansekerta yang terdiri dari dua
suku kata yaitu pari dan wisata. Kata pari berarti berulang-ulang atau berkali-
kali, sedangkan wisata berarti perjalanan atau bepergian. Jadi pariwisata berarti
perjalanan yang dilakukan secara berulang-ulang (Oka A. Yoeti :1996: 112).
Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Bab I
Pasal 1 ; dinyatakan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan
oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu
untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya
tarik wisata yang kunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan
pengertian daya tarik wisata menurut Undang-undang No. 10 Tahun 2009 yaitu
segala suatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa
keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang
menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata.
Berdasarkan penjelasan di atas, pada dasarnya wisata mengandung
unsur yaitu : (1) Kegiatan perjalanan; (2) Dilakukan secara sukarela;
(3) Bersifat sementara; (4) Perjalanan itu seluruhnya atau sebagian bertujuan
untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.
2. Definisi Objek Wisata
Pariwisata menurut UU No.10/2009 tentang kepariwisataan adalah
berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta
layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah
Daerah. Dalam Undang-undang ini menyebutkan pariwisata adalah segala
sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan
daya tarik wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan
pariwisata. Dengan demikian pariwisata meliputi:
1. Semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata.
2. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata seperti: kawasan wisata, Taman
26
rekreasi, kawasan peninggalan sejarah, museum, pagelaran seni budaya,
tata kehidupan masyarakat atau yang bersifat alamiah: keindahan alam,
gunung berapi, danau, pantai.
3. Pengusahaan jasa dan sarana pariwisata yaitu: usaha jasa pariwisata (biro
perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, konvensi, perjalanan insentif
dan pameran, konsultan pariwisata, informasi pariwisata). Usaha sarana
pariwisata yang terdiri dari akomodasi, rumah makan, bar, angkutan
wisata.
Pariwisata merupakan aktivitas perjalanan yang dilakukan untuk
sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan
bukan untuk menetap atau mencari nafkah. Dalam industri pariwisata ada
orang-orang yang berkunjung ke tempat tujuan wisata yang mereka inginkan.
Produk pariwisata terdiri dari beragam elemen. Kotler (2010: 230)
memaknai produk sebagai anything that can be offered to a market for
attention, acquisition, use or consumption that might satisfy a want or need,
includes physical objects, services, places, organisations and ideas. Dengan
kata lain, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar
guna menarik perhatiannya, perolehannya, penggunaan atau konsumsi di mana
bisa memuaskan keinginan dan kebutuhan.
Produk wisata bukanlah suatu produk yang nyata, produk ini
merupakan suatu rangkaian jasa yang tidak hanya mempunyai segi-segi yang
bersifat ekonomis, tetapi juga yang bersifat sosial, psikologis dan alam,
walaupun produk wisata itu sendiri sebagian besar dipengaruhi oleh tingkah
laku ekonomi. Ismayanti (2009: 147) memaparkan bahwa daya tarik wisata
merupakan fokus utama penggerak pariwisata di sebuah destinasi.
Jadi produk wisata merupakan rangkaian dari berbagai jasa yang saling terkait,
yaitu:
1. Jasa yang dihasilkan berbagai perusahaan (segi ekonomi) yang berupa
angkutan, penginapan, pelayanan makan minum, jasa tour dan sebagainya.
27
2. Jasa masyarakat dan pemerintah (segi sosial/psikologis) antara lain
prasarana umum, kemudahan, keramahtamahan, adat istiadat, seni budaya
dan sebagainya.
3. Jasa alam antara lain pemandangan alam, pegunungan, pantai, gua alam,
Taman laut dan sebagainya.
Menurut Medlik dan Middleton dalam Yoeti (1996: 28), yang dimaksud
dengan hasil industri pariwisata ialah semua jasa-jasa yang dibutuhkan
wisatawan semenjak ia berangkat meninggalkan tempat kediamannya, sampai
ia kembali ke rumah dimana ia tinggal. Produk wisata terdiri dari berbagai
unsur dan merupakan suatu package yang tidak terpisahkan, yaitu:
1. Objek pariwisata yang terdapat pada daerah-daerah tujuan wisata, yang
menjadi daya tarik orang-orang untuk datang berkunjung ke daerah
tersebut.
2. Fasilitas yang diperlukan di tempat tujuan tersebut, seperti akomodasi
perhotelan, bar dan restoran, hiburan dan rekreasi.
3. Transportasi yang menghubungkan negara/daerah asal wisatawan serta
transportasi di tempat tujuan ke objek-objek pariwisata.
Produk wisata yang baik harus dapat mendatangkan wisatawan sebanyak
banyaknya, menahan mereka dalam waktu yang lama, serta memberi kepuasan
kepada wisatawannya. Untuk mencapai hasil itu, beberapa syarat harus
dipenuhi yaitu:
1. Kegiatan dan objek yang merupakan atraksi itu sendiri harus dalam
keadaan yang baik. Untuk dapat memberikan kepuasan, atraksi wisata
harus dalam keadaan baik, baik atraksi yang berupa kegiatan seperti tarian
dan upacara, maupun atraksi yang berupa objek, seperti candi, keris dan
sebagainya.
2. Karena atraksi wisata itu harus disajikan di hadapan wisatawan, maka cara
penyajiannya harus tepat. Atraksi wisata boleh dikatakan berhasil kalau
menimbulkan kesan kepada wisatawan, sehingga merasa puas.
28
Kepuasan itu tidak hanya tergantung kepada keadaan atraksi wisata itu
sendiri, akan tetapi juga kepada caranya mempresentasikan di hadapan
wisatawan.
3. Objek wisata terintegrasi dengan syarat-syarat pariwisata lainnya, yaitu
jasa pelayanan, transportasi dan aktualisasi. Dengan membangun objek
wisata saja wisataan belum berdatangan. Objek wisata itu harus
diintegrasikan dengan syarat-syarat pariwisata lainnya, yaitu jasa
pelayanan, transportasi dan aktualisasi.
4. Dapat menahan wisatawan di tempat atraksi dalam waktu yang cukup
lama. Tujuan pembangunan pariwisata adalah tidak hanya mendatangkan
wisatawan sebanyak-banyaknya, akan tetapi juga untuk menahan mereka
selama mungkin. Dengan asumsi bahwa akan semakin besar keuntungan
yang diharapkan dari kehadiran mereka, yakni dengan semakin lamanya
wisatawan dapat bertahan di suatu objek wisata maka akan semakin
bertambah pula perputaran uang yang terjadi.
Pengembangan Obyek wisata alam sangat erat kaitannya dengan
peningkatan produktifitas sumber daya alam dalam konteks pembangunan
ekonomi, sehingga aspek kawasan hutan, pemerintah daerah, aspek
masyarakat, dan pihak swasta di dalam suatu sistem tata selalu dihadapkan
pada kondisi interaksi berbagai kepentingan yang melibatkanaspek kawasan
hutan, pemerintah daerah, aspek masyarakat, dan pihak swasta di dalam suatu
sistem tataruang wilayah. Dengan demikian konsep pembagunan pariwisata
berkelanjutan berbasis masyarakat menekankan yakni: 1) terpeliharanya mutu
dan berkelanjutan sumber daya alam dan budaya, 2) meningkatkan
kesejahteraan masyarakat lokal, 3) terwujudnya keseimbangan antara sumber
daya alam dan budaya, dan 4) kesejahteraan masyarakat lokal serta kepuasan
wisatawan.
29
3. Pemberdayaan Eknomi Masyarakat di Objek Wisata
Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi ditambah dengan
perubahan. Artinya, ada atau tidak adanya pembangunan ekonomi dalam suatu
negara pada suatu tahun tertentu tidak saja diukur dari kenaikan produksi
barang dan jasa yang berlaku dari tahun ke tahun, tetapi juga perlu diukur dari
perubahan lain yang berlaku dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi seperti
perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, peningkatan dalam
kesehatan, peningkatan dalam infrastruktur yang tersedia dan peningkatan
dalam pendapatan dan kemakmuran masyarakat. Pembangunan ekonomi dapat
diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita suatu
masyarakat terus menerus bertambah dalam jangka panjang.
Objek Wisata memiliki potensi ekonomi yang menjadi daya tarik
wisatawan diantaranya memiliki keindahan alam, keunikan masyarakat dan
kebudayaannya, lingkungan sosial dan kehidupan di sekitarnya. Objek Wisata
akan menjadi daya tarik jika dikenal ramai, lokasinya mudah dijangkau serta
namanya yang sudah familiar didunia maya baik di media cetak, elektronik,
media sosial dan juga media radio yang membuat namanya semakin dikenal
banyak orang. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat di objek
wisata terlihat makin menunjukkan perubahan. Pendapatan ekonomi
masyarakat disekitar objek wisata menunjukan indikasi peningkatan. Hal ini
terlihat secara bukti empiris bahwa pendapatan penduduk sekitar makin
menunjukkan tingkat kesejahteraannya.
Untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan
berbagai cara, diantaranya:
1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat
berkembang. Artinya bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat
dikembang. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya.
Pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya itu, dengan
mendorong dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya
serta berupaya untuk mengembangkannya.
30
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam hal
ini diperlukan langkah-langkah yang lebih positif, dan menciptakan iklim
dan suasana yang mendukung pemberdayaan. Bentuk dukungan
pemberdayaan ekonomi masyarakat berupa menyediakan akses ke dalam
sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti: modal, teknologi, informasi,
lapangan kerja dan pasar. Bentuk dukungan pemberdayaan ini menyangkut
pembangunan prasarana dan sarana dasar baik fisik, seperti: jalan,
pengadaan listrik dan fasilitas sosial lainnya yang dapat terjangkau
masyarakat lapisan bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan
dan lembaga kegiatan pelatihan.
Dengan demikian yang dimaksud pembangunan ekonomi di objek
wisata merupakan bentuk potensi untuk menguasai hajat hidup orang banyak
dengan menerapkan prinsip atau azas ekonomi kerakyatan. Pembangunan
ekonomi untuk masyarakat di objek wisata dapat dilakukan antara lain:
1) pengembangan pemberdayaan usaha kecil, 2) pemberdayaan koperasi dan
pengusaha mikro dan menengah, 3) pengembangan industri kecil dan
pembangunan prasarana dan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka
menunjang pembangunan usaha di objek wisata.
D. Kerangka Pemikiran
Profile masyarakat di objek wisata daerah pada umumnya masyarakat
yang memiliki mata pencaharian dengan pendapatan rendah, masyarakat desa
yang kental dengan kekerabatan, dan rata-rata pendidikan formal yang layak
masih kurang karena alasan keterbatasan biaya untuk pendidikan. Ciri lainnya,
hubungan sosial yang rendah dan juga kesempatan kerja yang kurang karena
keterbatasan keterampilan yang dimiliki masyarakat tersebut umumnya rendah.
Keberadaan objek wisata memberikan peluang yang luas atas layanan
wisata yang akan menghasilkan peningkatan ekonomi masyarakat sekitar.
Dengan dibukanya peluang usaha di objek wisata akan memberikan
kesempatan masyarakatnya untuk memberdayakan ekonomi melalui berbagai
usaha layanan wisata.
31
Berbagai layanan wisata yang dikelola oleh masyarakat di sekitarnya
memberikan kesempatan masyarakat untuk melakukan usaha ekonomi. Adanya
usaha dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat meningkatkan
penghasilan, yang pada akhirnya terjadi peningkatan kesejahteraan
masyarakatnya. Aktivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat, baik yang
dilakukan secara sendiri maupun berkelompok sebagai bentuk usaha ekonomi
masyarakat di objek wisata. Pendapatan yang diperoleh dari pemberdayaan
ekonomi masyarakat dimanfaatkan untuk mendukung pendidikan formal.
Dengan kata lain bahwa peningkatan penghasilan masyarakat dapat meningkat
pula jumlah peserta pendidikan formal.
Berikut proses logika konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam
mendukung pendidikan formal, diperjelas dengan kerangka berpikir penelitian
yaitu:
Gambar 1. Kerangka berpikir
Profile masyarakat di objek
wisata daerah pada umumnya:
-pendidikan rendah.
-pendapatan rendah
-pengangguran
-hubungan sosial rendah
-kurangnya kesempatan kerja
Keberadaan objek
Wisata
Kegiatan Pemberdayaan
ekonomi Masyarakat
secara mandiri maupun
kelompok
Masyarakat yang mampu memperbaiki dan meningkatkan penghasilan
Penunjang pendidikan formal
anggota masayarakat di objek
wisata.