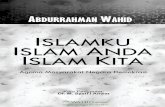ekonomi islam
Transcript of ekonomi islam
~ 1 ~
Diktat #1-Seri Ekonomi Islam
Ekonomi Islam:
Sebuah Pengantar
Oleh
Dr. M. Shabri Abd. Majid, M.Ec
Dosen Pengasuh
Matakuliah Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi
Universitas Syiah Kuala
Darussalam, Banda Aceh
e-mail: [email protected]
Handphone: +682160229553
DARUSSALAM-BANDA ACEH, 2011
~ 2 ~
BAB 1
SISTEM EKONOMI ISLAM
Ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang tingkah laku manusia dalam menggunakan
sumber ekonomi (buruh, tanah, modal dan entrepreneurship) untuk memenuhi kebutuhan
yang tidak terbatas. Dengan kata lain, ilmu ekonomi bertujuan untuk memenej sumber
ekonomi yang terbatas (limited resources) untuk memenuhi kebutuhan yang tidak
terbatas (unlimited wants). Akibat terbatasnya sumber ekonomi, maka manusia harus
membuat pilihan berdasarkan skala prioritas dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam
usaha memenuhi kebutuhannya itu, manusia harus berinteraksi dengan manusia yang
lain, alam, dan lingkungannya. Jadi, ilmu ekonomi itu meliputi aktivitas ekonomi dan
juga sebuah disiplin ilmu.
Apa pula yang dimaksud dengan sistem ekonomi? Menurut Webster‘s International
Dictionary, sebuah sistem adalah:
“A system is an aggegation or assemblage of object united by some form
of regular interaction or interdependence, a group of diverse units so
combined by nature or art as to form an integral whole and to
function,operate or move in unison to attain a specific goal and often in
obedience to some form of control; an organic or organized whole”.
Berdasarkan definisi di atas, maka sebuah sistem itu harus mengandungi tiga unsur
utama:
1. Sebuah sistem terdiri dari entitas dan komponen yang berbeda.
2. Kesemua entitas dan komponen tersebut saling beriteraksi satu sama lain secara
teroganisir.
3. Hasil dari interaksi tersebut akan mengarah kepada pemenuhan tujuan tertentu.
Merujuk pada definisi sistem di atas, maka sekarang kita dapat mendefinisikan sistem
ekonomi. Sistem ekonomi adalah:
“Any aggregation or assemblage of economic institutions that interact
with one another according to a particular plan to direct the economic
forces of society for the fulfillment of economic goals and objectives”
~ 3 ~
Jadi, sistem ekonomi adalah bagian kecil dari semua sistem sosial yang menjelaskan
tentang tingkah laku kekuatan ekonomi (economic forces) dalam masyarakat. Kekuatan
ekonomi ini berperan untuk memberi respon terhadap berbagai problema ekonomi.
Dalam memberi solusi terhadap problema ekonomi, kekuatan ekonomi ini memiliki
tingkah laku yang berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok
masyarakat lainnya. Tujuan ekonomi yang ingin diraih juga berbeda antara kelompok
masyarakat. Atau bisa jadi tujuannya sama, tapi maknanya mungkin berbeda antar
masyarakat.
Dalam merespon problema ekonomi dan juga mencapai tujuan tertentu, manusia itu
dipengaruhi oleh rangkaian hukum alam (natural laws) dan hukum sosial (social law).
Hukum alam ini adalah sama bagi semua masyarakat, tanpa mengenal suku, bangsa dan
kepercayaan. Contohnya, ―law of diminishing returns, diminishing marginal utility,
diminishing marginal rate of technical substitution dan law of increasing opportunity
cost‖ adalah semua hukum alam yang ada dalam semua masyarakat. Sedangkan, hukum
sosial dibentuk oleh budaya, tradisi, sejarah, iklim, norma-norma sosial, agama dan
‗worldview‘ masyarakat tertentu. Contohnya, Islam melarang memproduksikan arak,
tapi ianya bisa diproduksikan oleh non-muslim. Singkatnya, sistem ekonomi itu dapat
diilustrasikan seperti Diagram 1 di bawah ini.
Dari Diagram 1, kita dapati bahwa sistem ilmu ekonomi itu adalah bagian dari sub-sistem
ilmu-ilmu social (social sciences) yang yang lahir atas landasan ‗worldview‘ masyarakat
tertentu. Seperti sub-sistem politik dan sosial, sistem ekonomi terdiri dari berbagai
komponen seperti landasan filosofi, prinsip-prinsip operasional, dan tujuan yang berbeda.
Atas landasan filosofi itulah, fondasi mikro ekonomi itu dibangun sehingga membentuk
paradigma tersendiri. Akibat berbedanya semua komponen ini, maka lahirlah sistem
ekonomi yang berbeda seperti sistem ekonomi kapitalis, komunis/sosialis dan Islamis.
~ 4 ~
Diagram 1: Struktur Sistem Ekonomi
Sumber: Muhammad Arif (1985).
Dalam artikelnya ―Toward a Definition of Islamic Economics: Some Scientific
Considerations‖ yang dipublikasikan di ―Journal of Research in Islamic Economics‖,
Volume 2, Nomor 2, Tahun 1985, Muhammad Arif menjelaskan secara lebih terperinci
tentang perbedaan antara sistem ekonomi kapitalis, sosialis dan Islamis, seperti
diilustrasikan dalam Diagram 2 di bawah ini.
Berdasarkan Diagram 2 di atas, pada prinsipnya, sistem ekonomi itu di bangun atas
landasan paradigma yang berbeda. Sistem ekonomi sosial di bangun atas paradigma yang
diperkenalkan Karl Max (Marxian); sistem ekonomi kapitalis di bangun atas landasan
paradigma ekonomi pasar; sedangkan sistem ekonomi Islam di bangun atas landasan
paradigma Syari‘ah. Paradigma ekonomi ini pula di bangun atas fondasi filosofi yang
berbeda pula. Sistem ekonomi sosial di bangun atas landasan filosofi ―dialectical
materialism‖ berdasarkan gagasan Karl Marx. Menurut Karl Marx, pertumbuhan
ekonomi akibat kekuatan sumber ekonomi pada akhirnya akan mampu menghilangkan
kelas atau kasta dalam masyarakat (classless society).
~ 5 ~
Diagram 2: Dasar Fondasi Mikro Sistem Ekonomi
Sumber: Muhammad Arif (1985).
Selanjutnya, paradigm ekonomi kapitalis di bangun atas landasan filosofi ―utilitarian dan
individualistik‖ yang berlandaskan filosofi ―laissez faire‖. Filosofi ini memberikan
kebebasan yang luar biasa kepada pelaku ekonomi untuk memuskan kebutuhan yang
bersifat individualistik. Kapitalis percaya bahwa kalau individu itu hidupnya sudah
makmur, maka ekonomi secara makro pun akan maju. Sedangkan paradigma ekonomi
(Syari‘ah) Islam itu di bangun atas landasan filosofi ―kekhalifahan‖ (khalifah dan hamba
Allah) untuk meraih falah. Dalam ekonomi Syari‘ah, manusia itu hanya sebegai
pemegang amanah Allah yang dalam setiap tindak tanduknya harus berpedoman pada
aturan Allah dalam usahanya untuk meraih falah.
~ 6 ~
Ekonomi Islam: Definisi dan Karekteristinya
Apa itu ekonomi Islam? Apakah definisi ekonomi Islam itu sama dengan ekonomi
konvensional? Sudah tentu tidak! Karena di bangun atas landasan filosofi dan juga
memiliki tujuan yang berbeda dengan ekonomi konvensional, maka definisi ekonomi
Islam berbeda dengan ekonomi konvensional.
Menurut Hassanuzzaman (1984), ekonomi Islam itu adalah "…..the knowledge and
application of injunctions and rules of the Shari'ah that prevent injustice in the
acquisition and disposal of material resources in order to provide satisfaction to human
beings and enable them to perform their obligations to Allah and the society."
Sedangkan Akram Khan (1984) menyebutkan bahwa: “Islamic economics aims at the
study of human falah achieved by orgainising the resources of earth on the basis of
cooperation and participation.‖
Mohamed Aslam Haneef (1997) mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah: ―an
approach to interpreting and solving man‟s economic problems based on the values,
norms, laws and institutions found in, and derived from, the sources o knowledge in
Islam.‖
Sedangkan Muhammad Arif (1985) mendefinisikan ekonomi Islam ―… is the study of
Muslim's behaviour who organises the resources, which are a trust, to achieve falah.”
Dari beberapa definisi ekonomi Islam di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam
itu sangat menekankan pada pentingnya etika, moral, dan norma dalam memenej
sumberdaya ekonomi untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah). Walaupun
ekonomi Islam tidak bertujuan untuk memaksimumkan kepuasan (utility) dan
keuntungan (profit) seperti ekonomi konvensional, namun ekonomi Islam tidak melarang
pelaku ekonomi untuk mencari keuntungan. Namun keutungan materi itu bukanlah
segala-galanya. Keuntungan itu haruslah digunakan sebagai alat untuk mencari falah.
Dalam ekonomi Islam, sumber ekonomi ciptaan Allah yang terdiri dari tanah, buruh,
modal dan entrepreneurship itu tidak terbatas jumlahnya. Dengan kata lain, konsep
kelangkaan (scarcity) yang ada dalam ekonomi konvensional itu ditolak oleh ekonomi
Islam. Kerena kalau kita mengatakan sumberdaya ekonomi itu langka dan terbatas, maka
secara tidak langsung kita mengatakan bahwa Allah Yang Maha Perkasa itu lemah dan
~ 7 ~
tidak berdaya. Berikut ini adalah beberapa firman Allah SWT yang menegaskan bahwa
Allah telah menciptakan sumberdaya ekonomi yang tidak terbatas baik yang bersumber
dari langit, darat, dan bahkan dari lautan untuk digunakan secara optimal dalam
membangun ekonomi umat, dapat kita lihat dalam ayat-ayat berikut: "...dan jika kamu
menghitung nikmat Allah, niscaya tidak mampulah kamu menghitungnya..." (Q.S.
Ibrahim: 34); "Adalah Allah swt yang telah menciptakan langit dan bumi dan
menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu
berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera
bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah
menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai"; (Q.S. Ibrahim: 32); "...dan Dia
menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya
(sebagai rahmat) daripada-Nya..." (Q.S. al-Jatsiyah: 13); dan "Dan sesungguhnya Kami
telah menetapkan kamu (dan memberi kuasa) di bumi, dan Kami jadikan untuk kamu
padanya (berbagai jalan) penghidupan (supaya kamu bersyukur, tetapi) amatlah sedikit
kamu bersyukur." (Q.S. al-'Araf: 10).
Semua ayat di atas mengandung makna bahwa Allah swt telah membekali hidup
umatNya di dunia ini dengan sumberdaya ekonomi yang melimpah ruah. Berjalannya
roda ekonomi itu sangat bergantung kepada berbagai nikmat Allah sumberdaya
ekonomi), seperti nikmat matahari, bulan, bintang, hujan, minyak bumi, gas alam, emas,
intan permata, kesuburan tanah, lautan, dan berbagai nikmat Allah lainnya yang tidak
terkira jumlahnya. Tanpa semua nikmat ini, bisakah kita bayangkan apa yang akan
berlaku terhadap bumi ini bila sesaat saja diberhentikan Allah? Apakah kehidupan
manusia masih wujud? Masih dapatkah kita tertawa-riang, menyanyi, bersiul, berteriak,
dan senyum sebagaimana biasa? Apakah mungkin pembangunan ekonomi akan terjadi
tanpa semua ini? Jelas jawabannya adalah mustahil pembangunan ekonomi bisa terjadi
tanpa semua nikmat dan karunia Allah swt yang tak terkirakan itu.
Merujuk pada makna ayat-ayat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa,
sebenarnya, bukanlah sumber daya alam (nikmat) Allah swt yang terbatas, melainkan
kemampuan (ilmu) dan ketaqwaan manusialah yang terbatas untuk mengekplorasi dan
~ 8 ~
mendistribusikan sumber daya secara optimal dan adil. Penngunaan dan pendistribusian
sumberdaya alam secara tidak tepat dan adil oleh manusia yang serakah juga telah
menyebabkan sebagian manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pendek
kata, Islam tidak mengenal konsep kelangkaan (scarcity) sumber daya alam, yang ada
hanyalah terbatasnya kemampuan (ilmu) manusia untuk mengekplorasi sumber daya
alam dan tipisnya kadar keimanan dan tingkat ketaqwaan (ikhtiar/do‘a) umat dalam
usahanya untuk membangun ekonomi.
Karakteristik Unik Ekonomi Islam
Dari penjelasan di atas, jelas bahwa ekonomi Islam itu berbeda dengan ekonomi
konvensional baik pada tataran filosofi maupun tujuan. Berikut ini adalah ringkasan ciri-
ciri ekonomi Islam:
1. Ekonomi Islam dibangun atas landasan filosofi dan paradigma Syari‘ah.
2. Manusia sebagai pelaku ekonomi itu adalah berfungsi sebagai Khalifah.
Kecendrungan mementingkan kepentingan pribadi (selfish) manusia itu
haruslah berada dalam bingkai Syari‘ah.
3. Dalam ekonomi Islam adanya perpanjangan waktu (extended time horizon),
yaitu percaya akan ada hari Akhirat. Apapun yang dilakukan di dunia ini akan
diminta pertanggungjawabannya di hari Akhirat kelak.
4. Ekonomi Islam menganut sistem kepemilikan relatif (relative ownership).
Harta yang dimiliki manusia itu adalah milik mutlak Allah, sedangkan
manusia adalah pemegang amanah.
5. Pengambilan keputusan dalam ekonomi Islam itu dilakukan melalui ―syura‖
(musyawarah) atau kesepakatan bersama.
6. Adanya institusi al-Hisba dalam ekonomi Islam yang berperan untuk
mengawas pelaksanaan aktivitas ekonomi itu agar dijalankan dengan penuh
keadilan.
7. Adanya institusi zakat yang berperan mengumpulkan dana zakat dari orang
kaya untuk didistribusikan kepada mereka yang melarat.
8. Tidak seperti dalam ekonomi konvensional, riba itu dilarang dalam ekonomi
Islam.
~ 9 ~
Jadi jelas bahwa yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional bukan
hanya terletak pada adanya zakat dan tiadanya riba dalam ekonomi Islam [atau dapat
ditulis dengan rumus: Ekonomi Islam = Ekonomi Konvensional + Zakat – Riba]; tetapi
lebih dari itu. Ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional karena mereka di
bangun atas landasan filosofi yang berbeda, dan sudah tentu akan memiliki proses dan
tujuan yang berbeda pula.
Agar aktivitas ekonomi Islam itu benar-benar Islami, maka operasionalnya harus
berpandukan pada Syari‘ah. Untuk menjadikan sesuatu aktivitas itu Islami, tidak cukup
hanya dengan: ―membaca bismillah ketika memulai, menggunakan ayat al-Qur‘an dan
Hadist ditengah-tengahnya dan mengakhirinya dengan membaca Alhamdulillah‖. Hal ini
persis seperti disebutkan Syeik Idris (1987) berikut ini:
―How do we make some thing Islamic, including Islamic economic, of course, which is
already so? Or is it your intention merely to give each form of knowledge an Islamic
flavor by injection an “ayat” here, imposing a “Hadith” there, making an opening with
“bismillahi-rrahmani-rrahim” and a closing with “alhamdu lillahi rabbi-l‟alamin”?
Ekonomi Islam vs. Ekonomi Konvensional
Table 1 di bawah ini menjelaskan perbedaan antara ekonomi Islam dan ekonomi Islam
dalam menjawab pertanyaan penting ekonomi.
Table 1: Answers to Basic Economic Decisions by Different Economic Systems
Question What to produce? How to produce? For whom to produce?
Traditionalist What is believed can
support family
members (subsistence
level)
Produced in a traditional way,
focusing on agricultural and
mineral commodity
Distribution according to
the status. Barter play a
very important role in
distribution
Capitalist What business firms
believe people want and
firm will make profit
Producer decides how to
produce efficiently keeping in
view desire to make profit
Distribution according to
ability and inherited wealth
Socialist What central planners
believe socially
beneficial
Central planners decide keeping
in view the greater benefits of
the Society
Distribution according to
individual need determined
by central planners
Islamist What is permissible in
Shariah (Haram and
Halal) and needed? No
extravagance
Producer decides how to
produce efficiently keeping in
view desire to make profit and
public interest (maslahah)
Every one in the society is
provided with the basic
necessities by the state
~ 10 ~
Sedangkan Table 2 berikut menjelaskan perbedaan antara ekonomi Islam dan ekonomi
Islam dalam memenej aktivitas ekonomi.
Table 2: Salient Features of Different Economic Systems
Features Traditionalist Capitalist Socialist Islamist
Institution of property
ownership
Private
property by
tradition
Private
property
State owned
property
Both private and
public properties are
recognized
Motivational factor To survive
and retain the
power
Material
gain in this
world
Collective
welfare of
the society
Attain falah in this
world and hereafter
Organization decision
making & Coordination
mechanism
Tradition or
custom
Market
mechanism
Central
planning
Market mechanism
with positive role
of the state
~ 11 ~
BAB 2 EKONOMI ISLAM:
SOLUSI TERHADAP BERBAGAI PENYAKIT EKONOMI
Diskursus tentang sistem ekonomi yang paling ideal dan sesuai bagi umat sudah sejak
lama dimulai dan hingga detik ini belum lagi berakhir. Ini dapat kita baca dari lansiran
berita-berita di berbagai media massa tentang malapetaka ekonomi yang terjadi akibat
kelemahan sebuah sistem ekonomi. Setelah memudarnya sistem ekonomi komunis
bermula pada kehancuran negara Uni Soviet, maka kini giliran sistem ekonomi kapitalis
pula yang sentiasa mendapat sorotan dan kritikan. Seringnya timbul penyakit ekonomi,
seperti pengangguran, inflasi, dan bahkan krisis ekonomi di negara-negara penganut
ekonomi ala kapitalis merupakan bukti bahwa sistem ekonomi kapitalis bukanlah sebuah
sistem ekonomi yang ideal. Tulisan ini ingin menganalisa eksistensi sistem ekonomi
kapitalis dan komunis serta perbandingannya dengan sistem ekonomi Islam.
Sistem Ekonomi Kapitalis dan Komunis
Kita tidak menafikan bahwa ekonomi merupakan suatu bagian penting dalam kehidupan
bermasyarakat. Oleh itu, terealisasinya kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam sebuah
negara sangat ditentukan oleh eksistensi sistem ekonomi negara yang stabil dan mantap.
Dalam masyarakat, setidaknya, ada dua pemikiran azas yang mempengaruhi sistem
ekonomi negara. Pertama, prinsip individu dengan liberalis dan kapitalisnya. Kedua,
prinsip kebersamaan dengan sosialisnya. Berdasarkan kedua pemikiran azas inilah telah
lahir sistem-sistem ekonomi yang dikenal dunia saat ini, seperti sistem ekonomi pasar
bebas (kapitalis) dan ekonomi sentralistis (komunis). Dalam bukunya "An inquiry into the
Nature and Causes of Wealth of Nations", bapak pengasas ekonomi, Adam Smith (1776)
telah menganalisa semua permasalahan mendasar ekonomi kapitalis. Di dalam bukunya
itu, Adam Smith berhujah bahwa penggerak perekonomian suatu negara ialah individu-
individu, sehingga syarat mutlak berhasilnya perekonomian ialah terletak pada kebebasan
yang tidak terbatas yang diberikan negara kepada para individu atau pengusaha.
Penggunaan faktor-faktor ekonomi secara pribadi untuk keuntungan pribadi, pembukaan
pasar-pasar bebas global, penentuan harga barang dan jasa di pasar oleh mekanisme
~ 12 ~
penawaran dan permintaan (mekanisme pasar), keuntungan individu merupakan
penyumbang pembangunan ekonomi, dan terbatasnya peran pemerintah dalam
mengontrol sistem perekonomian negara adalah di antara ciri-ciri utama ekonomi
kapitalis. Merujuk pada ciri-ciri sistem kapitalis ini, sistem ini jelas memberikan peluang
yang seluas-luasnya bagi mereka-mereka yang memiliki modal yang banyak untuk
meraih keuntungan maksimum dengan memanfaatkan kelemahan golongan tidak
bermodal (miskin). Semua pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi ini cendrung
mementingkan diri sendiri (selfishness) tanpa peduli kesejahteraan hidup orang lain.
Apapun usaha dan kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam sistem ekonomi ini, semunya
dilakukan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri dengan sebebas-bebasnya tanpa
campur tangan pemerintah. Akibatnya, dalam sistem ekonomi kapitalis, golongan kaya
akan semakin kaya-raya dan golongan miskin akan semakin papa-kedana.
Kelemahan sistem ekonomi kapitalis di atas—yang menjadikan jumlah pemilikan
―materi‖ sebagai pengukur keberhasilan individu dan negara—telah mengakibatkan
lahirnya sistem ekonomi komunis atau sosialis yang sangat menfokuskan kesejahteraan
kolektif (bersama) yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah. Latar belakang lahirnya
ekonomi komunis dapat kita baca dari teori Marxis–Lenin (1974) yang dituangkan dalam
bukunya bertajuk: ―Politische Oekonomie des Kapitalismus und des Sozialismus‖ sebagai
berikut: "...kaum buruh dapat melepaskan dirinya sendiri, hanya apabila kepemilikan
secara kapitalis terhadap barang-barang produksi dihilangkan dan sebagai gantinya ialah
dibentuknya kepemilikan secara sosial".
Pemikiran inilah yang menjadi azas dan prinsip kepemilikan bersama terhadap faktor-
faktor produksi dalam sistem ekonomi komunis. Kepemilikan bersama terhadap faktor-
faktor produksi, seperti tanah, modal, buruh, dan kewiraswataan adalah dimaksudkan
untuk kepentingan bersama. Jadi, dalam sistem ini, keuntungan pribadi secara materi
bukan merupakan pendorong bagi para pelaku ekonomi untuk memenuhi perencanaan
pembangunan negara, melainkan tanda-tanda jasa dari negara. Para pelaku ekonomi tidak
memiliki ruang gerak yang bebas dalam melakukan berbagai aktivitas ekonominya,
banyaknya produksi juga harus disesuaikan dengan keperluan konsumen, untuk ini
~ 13 ~
dibentuk neraca produksi yang disesuaikan oleh neraca keperluan produksi tersebut,
semua perencanaan pembangunan, strategi perekonomian dan implementasi serta
pelaksanaan aktivitas ekonomi, semuanya ditentukan dan dikontrol sebaik-baiknya oleh
pemerintah. Singkatnya, semua aktivitas ekonomi dalam sistem ekonomi komunis mutlak
diatur oleh pemerintah, sedangkan individu tidak memiliki kebebasan sama sekali.
Kesejahteraan ekonomi mutlak berada di tangan pemerintah.
Kedhaifan Sistem Ekonomi Kapitalis dan Komunis
Seperti dikatakan sebelumnya, sistem ekonomi komunis atau sosialis kian simakin pudar.
Banyak negara-negara yang dulunya menganut sistem ini, kini telah menganut sistem
ekonomi yang lebih terbuka, iaitu ekonomi kapitalis. Hal ini, diantaranya, disebabkan
oleh tidak produktifnya sistem ini (sosialis) di era globalisasi. Dimana untuk
memproduksikan suatu barang dan jasa dibutuhkan berbagai bahan mentah (raw
material) yang tidak semuanya dapat dipenuhi bersumber dari dalam negeri, dan bahkan
kesukaran untuk mengimportnya dari luar negeri dengan harga yang berpatutan (murah).
Banyak negara penganut ekonomi sosialis tidak mampu mencapai kepuasan pribadi
rakyatnya mulai dari masalah pembayaran upah buruh hingga ke masalah pengembangan
karier pelaku ekonomi. Kemudian, kelemahan utama sistem ini adalah tidak memberi
pengakuan terhadap kelebihan pemilikan skills, bakat, dan sumbangsih yang diberikan
para individu yang hidup dalam sistem ini. Bagaimanapun kerasnya usaha mereka dengan
skills dan bakat yang tinggi untuk memajukan ekonomi negara, namun mereka hanya
berhak mendapat kesejahteraan (pendapatan) yang sama-rata dengan orang lain yang
malas bekerja dan sama sekali tidak mempunyai skills. Inilah ketidakadilan terbesar yang
berlaku dalam sistem ekonomi komunis ini. Karena, dalam Islam, keadilan itu bukanlah
berarti bahwa negara harus membagi sama-rata hasil pembangunan tanpa
mempertimbangkan jerih payah dan usaha yang disumbangkan pada negara, melainkan
keadilan dalam Islam itu adalah membagi hasil pembangunan sesuai dengan jerih payah
dan usaha yang disumbangkan. Ini tentunya, mereka yang rajin bekerja dengan memiliki
skills dan bakat yang tinggi akan mendapat hak untuk menikmati hasil pembangunan
dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang malas bekerja dan
tidak berbakat dan memiliki skills. Ketidakadilan sistem ini dalam membagi hasil
~ 14 ~
pembangunan pasti akan menyebabkan orang-orang yang rajin bekerja akan semakin
malas bekerja—akibat tidak mendapat kompensasi proportional dengan sumbangan jerih
payah dan kerja yang mereka berikan pada negara—dan yang malas bekerja, sudah tentu,
akan terus semakin malas.
Sementara itu, di negara-negara yang menganut sistem kapitalis, kebebasan terhadap
kepemilikan faktor-faktor produksi dan harta-benda juga akan menimbulkan berbagai
masalah, antara lain ialah terkonsentrasinya pemilikan kekayaan negara pada satu atau
segelintir masyarakat saja, khususnya mereka yang memiliki modal yang banyak.
Konsekuensinya, sistem ini akan semakin memperlebar ―gap” antara si kaya dan si
miskin yang, pada gilirannya, akan merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat.
Seperti berlaku di Indonesia, misalnya, golongan kaya-raya bahkan pada kenyataannya
telah menguasai mekanisme penentuan harga di pasar, yang secara teori seharusnya
terbentuk melalui mekanisme penawaran dan permintaan antara konsumen dan produsen.
Dengan aksi monopolinya, kelompok ini semakin merajalela dalam memperkaya dirinya
sendiri tanpa memperhatikan kesejahteraan golongan menengah ke bawah yang hidupnya
dari hari ke hari semakin melarat, kebebasan dan keuntungan individu sebagai pendorong
lajunya roda perekonomian negara telah mengakibatkan pudar dan bahkan hilangnya
nilai-nilai rasionalitas masyarakat dalam membangunan negara, dan bahkan telah
menjadikan hawa nafsu sebagai acuan dalam berbagai tindakan mereka. Kalau ini telah
berlaku, maka kehancuran akan bermula, begitu Allah SWT menjanjikan dalam
firmanNya: ―Dan kalaulah kebenaran itu tunduk menurut hawa nafsu mereka, nescaya
rusak binasalah langit dan bumi serta segala isinya...‖ (Q.S. al-Mukminun: 71). Bila kita
melihat realitas sekarang dengan menatapi apa yang telah dan sedang berlaku di hampir
semua negara-negara penganut ekonomi kapitalis dan sosialis dewasa ini, maka janji
Allah SWT di atas telahpun menjadi kenyataan. Perekonomian negara-negara yang
dikuasai oleh dorongan hawa nafsu, satu-persatu telah mengalami kelesuan, kemorosotan
dan bahkan kehancuran. Seperti krisis ekonomi dan politik yang belum berakhir terjadi di
Indonesia, kebanyakannya disebabkan oleh bisnis-bisnis spekulatif yang dilakukan oleh
segelintir golongan yang tidak bertanggung jawab dengan mengekploitasi kekayaan
negara, tentunya, dengan memanfaatkan kelemahan sistem perekonomian pada umumnya
~ 15 ~
dan sistem perbankan Indonesia pada khususnya yang memiliki kemiripan dengan sistem
ekonomi kapitalis. Begitu juga dengan krisis ekonomi global 2007 yang bermula di
Amerika Syarikat, semuanya terjadi akibat keserakahan manusia bermodal untuk
mengeksploitasi mereka yang lemah.
Selanjutnya, akibat kebebasan tanpa batasan dalam sistem ekonomi kapitalis telah
memposisikan para golongan konglomerat (tycoons) sebagai penguasa ekonomi negara.
Perkara ini, misalnya, dapat kita lihat dari perkembangan ekonomi negara Indonesia
dimana dengan aksi-aksi permainan kotor (malpractices) di sektor keuangan, penetapan
harga barang primer yang tidak berpatutan di tengah krisis ekonomi, telah menyebabkan
kelompok konglomerat ini menjadi sangat dominan dalam menentukan berbagai
kebijakan ekonomi negara dan bahkan seringkali mampu mendesak pemerintah agar
kebijakan ekonomi negara tersebut semakin memihak kepada kepentingan mereka. Sifat
ini secara perlahan-lahan tapi pasti akan memudarkan dan sekaligus menghilangkan nilai-
nilai etika sosial dalam masyarakat. Bila sifat ini terus subur berlaku dalam masyarakat,
maka akan menutup kemungkinan bagi si miskin atau orang yang secara fisik tidak
mampu untuk hidup secara layak dan makmur. Sementara itu, dibukanya pintu untuk
pasar internasional secara bebas sesuai dengan kehendak sistem ekonomi kapitalis akan
menimbulkan kolonialisme gaya baru yang akan memonopoli kekayaan alam negara
tanpa peduli kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Khususnya di negara-negara
berkembang seperti di Asia, kebijakan-kebijakan dan prioritas ekonomi kapitalis ialah
pengeksploitasian kekayaaan negara dengan mengabaikan nilai-nilai sosial di dalam
masyarakatnya. Inilah sebabnya para kapitalis berhaluan keras (ekstrim) berhujah bahwa:
―kesejahteraan ekonomi itu dengan mudah akan dapat direalisasikan secara maksimal jika
tanpa dihalang oleh paraturan-peraturan‖. Dengan kata lain, para pelaku ekonomi baik
individu dan pengusaha harus diberikan kebebasan yang seluas-luasnya dalam melakukan
berbagai aktivitas ekonomi dalam rangka membangun ekonomi negara. Sikap dan prinsip
sistem kapitalisme seperti ini telah mengakibatkan memudar dan bahkan menghilangnya
nilai-nilai etika-sosial (akhlaqul karimah) dalam masyarakat kapitalis, dan bahkan
mereka telah dikuasai oleh hawa nafsu yang kapan saja siap mengheret umat manusia ke
lembah kepapaan dan kehancuran.
~ 16 ~
Sebenarnya, cukup banyak kritikan-kritikan lain yang dilontarkan terhadap kedua sistem
ekonomi di atas, walaupun dalam realitasnya jarang sekali salah satu dari ke dua sistem
ini dianut secara sempurna oleh negara tertentu di dunia. Sebagai contoh sistem ekonomi
―Soziale Marktwirtschaft‖ di Jerman, di samping menganut sistem pasar bebas (kapitalis),
sistem ini juga memiliki jaringan sosial yang padu (komunis). Pendek kata, semua
kritikan yang dilontarkan terhadap ke dua sistem ekonomi besar dunia ini menunjukkan
bahwa sistem-sistem ekonomi ini tidak terlepas dari berbagai kelemahan dan kedhaifan
dalam menawarkan solusi terhadap permasalahan ekonomi global.
Ekonomi Islam: Sebuah Solusi?
Sebagai agama komprehensif (syumul), Islam tidak hanya mengatur persoalan
menyangkut peribadatan semata, malah sebagai ―the way of life‖ Islam juga mengatur
berbagai masalah ekonomi, dimulai dari pengaturan faktor-faktor produksi dan
hubungannya dengan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, seperti terakam
dalam ayat-ayat berikut yang, masing-masing, bererti: ―Dan Dialah yang menjadikan
kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian
(yang lain) beberapa derjat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikanNya
kepadamu...‖ (Q.S. al-An‘am:165); ―Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para
Malaikat: „Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi‟...‖
(Q.S. al-Baqarah:30); dan ―...dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di
bumi...” (Q.S. al-Naml: 62). Kata-kata ―menjadikan manusia sebagai khalifah‖, seperti
disebutkan dalam ayat-ayat di atas, menurut para mufassirin (ahli tafsir), bermakna
bahwa Allah SWT telah menjadikan manusia berkuasa di atas muka bumi ini. Kekuasan
manusia ini, tentunya, tidak terbatas dalam aspek-aspek tertentu saja seperti aspek
peribadatan, tetapi juga meliputi aspek sosio-ekonomi, politik, budaya, dan berbagai
aspek kehidupan umat lainnya.
Dalam hal kekuasaan di bidang ekonomi, khususnya kepemilikan terhadap faktor-faktor
produksi, seperti tanah, modal, buruh dan kewiraswastaan adalah sesuatu yang dihalalkan
Allah SWT bagi manusia sebagai khalifah-Nya berteraskan nilai-nilai Islami. Ini
bermaksud bahwa kepemilikan mutlak (absolute ownership) dalam Islam hanya semata-
~ 17 ~
mata milik Allah SWT, dan manusia hanya merupakan ―pemegang amanah‖ (trustee)
terhadap pemilikan Allah SWT untuk digunakan sesuai dengan peraturan syara‘ demi
kemaslahatan orang banyak. Ini juga berimplikasi bahwa manusia juga diserukan untuk
sentiasa menempuh jalan yang telah digariskan Islam dalam melaksanakan aktivitas
ekonomi, seperti dalam proses produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa.
Tegasnya tuntutan Islam agar umatnya senantiasa menjalankan berbagai kegiatan
duniawi berlandaskan Syari‘at jelas terlihat dari keharusan setiap individu Muslim untuk
mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang mereka lakukan di dunia ini pada hari
akhirat kelak. Di Mahkamah Ilahi, kita tidak berpeluang untuk memberi saksi palsu dan
menipu Allah SWT sebab semua catatan amalan baik dan buruk kita telah sangat rapi dan
komplit dicatat satu-persatu oleh dua Asisten Ilahi yang sangat loyal, Malaikat Raqib dan
Atid. Perkara ini seperti ditegaskan Allah SWT dalam firman-firmanNya, yang
bermaksud seperti berikut: ―(yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat amal
perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri.
Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada dekatnya malaikat pengawas
yang selalu hadir" (Q.S. Qaaf: 17-18); "Dan katakanlah wahai Muhammad saw:
Beramallah kamu (akan segala yang diperintahkan), maka Allah dan Rasul-Nya serta
orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan" (Q.S. at-Taubah: 105); dan
―…sesungguhnya kamu akan ditanya kelak tentang apa yang kamu kerjakan‖ (Q.S. an-
Nahl: 93). Oleh karena itu, hak kepemilikan terhadap faktor-faktor produksi pada
khususnya dan harta-benda pada umumnya yang dianugerahkan Allah SWT kepada
manusia sebagai pemegang amanah-Nya haruslah benar-benar dijalankan berteraskan
nilai-nilai Qur‘ani demi kemaslahatan umat, dan manusia sekali-kali tidak berupaya
untuk menipu Sang Penciptnya, Allah Rabb al-Jalil.
Cara Mendapat Hak Pemilikan
Secara umum, hak milik dalam Islam dapat diperolehi melalui beberapa cara, seperti
melalui bekerja dan harta warisan. Hal ini seperti sabda Rasulullah saw yang
mengandungi makna: "Barang siapa memakmurkan sebidang tanah bukan milik
seseorang, maka dialah yang lebih berhak memiliki tanah itu" (al-Hadis). Selanjutnya,
~ 18 ~
kepemilikan terhadap harta juga berlaku melalui pewarisan, pemberian (hadiah),
penjualan, wasiat dan berbagai cara pemindahan hak kepemilikan lainnya.
Islam mengenal hak kepemilikan terhadap harta dan faktor-faktor produksi sebagai tugas
sosial bagi pemilik hak tersebut dalam batas-batasnya sebagai khalifah di bumi ini.
Sebagai khalifah fil-Ard, manusia diserukan untuk menegakkan makruf dan
mengenyahkan munkar, termasuk dalam mengelola faktor-faktor produksi yang telah
dianugerahkan Allah SWT kepada manusia. Penentuan harga secara bebas tanpa adanya
unsur monopoli merupakan ciri khas terbentuknya mekanisme harga dalam sistem
ekonomi Islam. Namun, perlu dicatat bahwa, dalam sistem ekonomi Islam pemerintah
berhak melakukan intervensi pasar apabila telah terjadinya kejahilan ekonomi, seperti
monopoli, penyeludupan, perjudian, hyperinflasi (membumbungnya harga barang dan
jasa di luar batas-batas harga yang berpatutan) dan berbagai aktivitas ekonomi yang
bertentangan dengan nilai-nilai keadilan ekonomi Islam lainnya. Tidak seperti ekonomi
kapitalis yang sama sekali bebas dari campur tangan pemerintah dan sistem ekonomi
komunis yang semua aktivitas ekonominya diatur sepenuhnya oleh pemerintah, sistem
ekonomi Islam berada di antara ke dua sistem ini dimana wujudnya kebebasan ekonomi
dalam batas-batas tertentu dan campur tangan pemerintah hanya dibenarkan sebatas
untuk mengawal kejahilan ekonomi dalam batasan-batasan tertentu pula. Pendek kata,
pemerintah mempunyai hak dan tanggung jawab untuk menstabilkan perekonomian
negara dalam sistem ekonomi Islam.
Peran Pemerintah dalam Ekonomi Islam
Urgensi peran aktif pemerintah untuk memastikan kestabilan ekonomi negara telah
direkam Allah SWT dalam ayat berikut yang bermakna: "Sesungguhnya Kami telah
mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami
turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat
melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang
hebat dan berbagai manfaat bagi manusia (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan
supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasulNya padahal
Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha perkasa" (Q.S. al-
~ 19 ~
Hadith: 25). Ayat ini telah diinterpretasikan secara berbeda oleh para mufassirin.
Kaitannya dengan usaha untuk mewujudkan sistem ekonomi yang stabil dan berkeadilan,
Muhammad al-Mubarak (1972) di dalam bukunya "Nizam al-Islam al-Iqtisadi" telah
mengintepretasikan bahwa untuk memastikan kestabilan dan keadilan ekonomi, maka
Islam membenarkan negara untuk menggunakan kekuatan (besi) melalui penegakan
hukum. Sebagai contoh, apabila ada individu tertentu atau sekelompok anggota
masyarakat yang menyimpan (ihtikar) barang keperluan masyarakat awam yang sangat
mendesak (urgent needs), maka pemerintah berhak memaksa para penyimpan/penyorok
barang untuk menjual barangnya dengan "harga yang adil", meminjam istilah Ibn
Taymiyah, yaitu pada tingkat harga yang sama (qimat-al-mithl) dengan barang sejenis di
pasar. Demi mewujudkan kepentingan orang banyak (Maslahah al-Ammah), bahkan
Muhammad al-Ghazali (1952) dalam bukunya "Al-Islam wa al-Awda' al-Iqtisadiyyah"
mengatakan bahwa negara berhak membatasi kebebasan seseorang individu demi untuk
menyelamatkan kepentingan dan kemaslahatan orang ramai. Begitu juga bila orang kaya
menolak untuk mengeluarkan hak si miskin (zakat), maka negara berkewajiban untuk
memaksa orang kaya agar memenuhi hak si miskin tersebut. Tindakan memerangi umat
Islam yang ingkar membayar zakat ini dapat kita rujuk pada tindakan Khalifah Abu
Bakar as-Siddiq RA, beberapa hari setelah kemangkatan Rasulullah SAW, yang dikenal
dengan Perang Siffin. Alasan utama kenapa Khalifah al-Rasyidin pertama ini memerangi
mereka adalah seperti kata beliau sendiri: "Demi Allah SWT aku akan memerangi mereka
yang membedakan di antara sembahyang dan zakat karena zakat adalah tuntutan
terhadap harta. Demi Allah SWT, seandainya mereka enggan membayar zakat itu,
sedangkan mereka pernah membayarnya kepada Rasulullah dulu, aku tetap akan
memerangi mereka." (H.R. Ibn Hajar dan Bukhari).
Tindakan pemaksaan ini haruslah menjadi agenda negara dalam upayanya untuk
mensejahterakan ekonomi masyarakat miskin, sebab kegagalan negara dalam memenuhi
keperluan si miskin, menurut Abdul Qadir Audah (1977) di dalam bukunya "Al-Mal wa
al-Hukm fi al-Islam" adalah merupakan pertanda negara telah membenarkan terjadinya
penindasan terhadap hak-hak kaum miskin oleh kaum kaya. Pengabaian hak si miskin
~ 20 ~
yang telah dijamin Allah SWT oleh negara jelas telah melanggar aturan Ilahiah yang
tidak dibenarkan agama.
Pemerintah dalam memenej negara, menurut mayoritas para Fukaha (ahli Fikah),
setidaknya harus memproteksi empat hak dan kebebasan fundemantal setiap individu
Muslim (warga negara).
1. hak dan kebebasan untuk hidup;
2. hak dan kebebasan beragama;
3. hak dan kebebasan untuk mencari dan memiliki harta; dan
4. hak dan kebebasan untuk mengaktualisasi martabat dan harga diri.
Agar ke-empat unsur di atas terpenuhi, maka pemerintah berkewajiban untuk:
1. Menjamin terwujudnya pendistribusian kekayaan negara yang berkeadilan. Untuk
itu, maka Islam telah meletakkan zakat, inter alia, sebagai instrumen kebijakan
fiskal yang sangat penting dalam mewujudkan pendistribusian pendapatan yang
berkeadilan di antara sesama warga negara.
2. Menyediakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya sehingga ekonomi berada
dalam kondisi guna tenaga penuh (full-employment). Dalam hal ini, pemerintah
hendaklah membuka training dan program ketrampilan tertentu (seperti,
entrepreneurial skills) sehingga kalaupun para pencari kerja yang siap pakai
(ready employed) tidak mendapat peluang kerja di instansi pemerintahan dan
swasta, maka dengan bekal training yang mereka miliki, dengan sendirinya, akan
memudahkan mereka untuk memulai bisnis sendiri.
3. Memastikan pelaksanaan ―‗amar makruf wa nahi munkar”. Hal ini, diantaranya,
sesuai dengan firman Allah SWT dalam ayat berikut yang, masing-masing,
berarti: "Yaitu orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka
bumi niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat
yang makruf dan mencegah yang munkar, dan kepada Allahlah kembali semua
urusan" (Q.S. al-Hajj: 41) "Dan hendaklah ada diantara kamu yang menyeru
~ 21 ~
kepada kebaikan, meyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang
munkar...” (Q.S. Ali Imran: 104).
Agar penegakan ―amar makruf wa nahi munkar” dalam ekonomi Islam benar-
benar terlaksana, maka dalam melaksanakan tugas suci ini hendaklah negara
menunjukkan individu-individu yang berkompeten (berkelayakan), bertanggung
jawab, dan tidak ragu-ragu dalam menghukum dan memecat mereka yang berlaku
curang dan berlaku tidak adil. Seterusnya, negara tidak dibenarkan untuk
mengamalkan diskrimanasi hukum terhadap warganya yang melakukan kriminal
ekonomi. Siapapun yang bersalah, tanpa melihat kedudukan, kekayaan,
keturunan, tingkat pendidikan, dan pengaruhnya dalam masyarakat, haruslah
dihukum dengan standar hukuman (penalty) yang berkeadilan.
Pentingnya keagresifan pemerintah dalam mewujudkan kestabilan ekonomi, dapat
kita lihat dari besarnya perhatian Khalifah Ali bin Thalib RA dalam mengawasi
harga barang, timbangan dan ukuran barang yang digunakan para pedagang dan
pemborong (dealers) di pasar pada masa itu. Hal ini seperti disebutkan Dr. Abdul
Qadir Husaini (1966) di dalam bukunya, Arab Administration, "...dimana sejak
dari awal pemerintahan Islam, Khalifah Ali bin Abi Thalib RA senantiasa telah
terjun langsung sendiri ke pasar Kufah untuk mengontrol timbangan yang
digunakan dan beliau memastikan bahwa benar-benar tidak ada seorangpun
yang merasa dirugikan...".
4. Memerangi institusi riba, monopoli, perjudian (gambling), dan semua tindakan
yang bertentangan dengan syari‘at Islam lainnya. Dalam hal ini, pemerintah harus
senantiasa mengadakan pengecekan mendadak (spot check) ke pasar-pasar dan ke
berbagai tempat aktivitas ekonomi dijalankan. Dan bila terjadi kejahilan ekonomi,
maka pemerintah harus mengambil tindakan tegas tanpa pilih kasih dan ber-
korupsi, kolusi, dan nepostime (ber-KKN) dengan penjahat ekonomi. Tindakan
tegas ini sangat perlu diambil pemerintah dalam rangka menutup peluang dan
ruang gerak pelaku kejahatan ekonomi agar tidak mengulangi lagi kejahatan
~ 22 ~
mereka yang sangat merugikan umat. Singkatnya, pemerintah dalam semua
kebijakan ekonominya tidak bersifat pilih kasih terhadap rakyat jelata. Pemerintah
harus menyayangi dan menghargai rakyatnya sama rata (secara adil) sebagaimana
ia menyayangi dan menghargai setiap anggota tubuhnya sendiri, dan bahkan
menempatkan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadinya. Siapa
saja yang melanggar hukum harus ditindak dengan hukuman yang berkeadilan
tanpa membedakan status, keturunan, kekayaan, dan jasanya kepada rakyat dan
negara. Karena sifat pilih kasih baik dalam memprioritaskan alokasi kesejahteraan
maupun dalam menegakkan hukum (law enforcement) kepada rakyatnya akan
menyebabkan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap kepemimpinannya, dan
bahkan akan mengundang malapetaka. Kemudian, dalam bertindak pemerintah itu
haruslah mampu mengikuti jejak-jejak praktek Rasulullah SAW dalam
menegakkan hukum, seperti sabda Rasulullah SAW berikut, yang bermakna:
―Sungguh Allah SWT telah membinasakan umat sebelum kamu, karena apabila
ada di antara orang besar mencuri dibiarkan saja, tetapi jika orang kecil yang
mencuri dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Demi Allah SWT yang jiwaku
berada di tanganNya, andaikata anakku Fathimah, Putri Rasullullah mencuri
pasti akan ku potong tangannya‖ (al-Hadits).
5. Menjamin semua warganya benar-benar mendapat keadilan melalui sistem
peradilan yang adil, efektif dan efisien dengan menggunakan standard dan moral
hukum yang sama tanpa mengenal istilah diskriminasi hukum. Singkatnya, Islam
mendorong kebebasan dan menentang peraturan-peraturan atau birokrasi yang
berlebih-lebihan terutama menyangkut aktivitas ekonomi dan perdagangan. Ini
semua bertujuan untuk memartabatkan ekonomi yang berkeadilan benar-benar
dirasakan oleh setiap warganya.
Batasan Peran Pemerintah
Walaupun demikian tidak berarti bahwa dalam mewujudkan kestabilan ekonomi yang
berkeadilan, pemerintah bisa bertindak sekehendak hatinya tanpa mengenal batasan-
batasan hukum. Menurut Yusuf (1971) dalam ―Economic Justice in Islam”-nya,
~ 23 ~
mengatakan bahwa dalam mewujudkan ekonomi yang stabil dan berkeadilan, pemerintah
haruslah memperhatikan batasan-batasan tertentu, diantaranya, adalah:
1. Pemerintah tidak dibenarkan bertindak ―immoral” yang sangat merugikan
warganya. Penggunaan kekuasaan dan hak istimewa untuk memonopoli
keuntungan, misalnya, memungut pajak secara berlebihan dan tidak berazas
dengan maksud untuk melindungi segelintir produsen atas alasan industrialisasi
yang sangat merugikan masyarakat umum adalah perbuatan tercela yang sangat
keras ditentang Islam. Atas alasan itulah, Islam tidak menggalakkan pemungutan
pajak secara tidak langsung (indirect tax) karena cara ini terkesan menipu dan
memaksa rakyat untuk membayar pajak tanpa sepengetahuan mereka. Sebaliknya,
Islam sangat menggalakkan pemungutan pajak untuk dilakukan secara langsung
(direct tax), karena pembayaran pajak secara langsung oleh masyarakat jelas
merupakan kontribusi yang dilakukan secara sadar dan sepengetahuan mereka
demi kepentingan umat.
2. Dalam pelaksanaan aktivitas bisnis, pemerintah hendaknya tidak membebankan
warganya untuk membayar biaya-biaya administrasi, surat izin transaksi dan
bisnis lainnya bila mereka melakukan aktivitas bisnis yang memerlukan perizinan
dan pengesahan (endorsement) dari pemerintah. Pemerintah hendaklah benar-
benar menciptakan keadaan bisnis yang kondusif dan bebas biaya, bukan
sebaliknya mematikan bisnis mereka dengan cara memungut biaya-biaya yang
tidak pada tempatnya. Begitu juga, ketika warga negaranya ingin mencari
keadilan, hendaklah pemerintah membebaskan biaya pengadilan sehingga
keadilan itu betul-betul wujud dalam masyarakat.
Seperti disebutkan sebelumnya, kewajipan berzakat merupakan bukti bahwa Islam sangat
memerhatikan kesejahteraan semua lapisan masyarakat, terutama para kaum lemah
ekonomi (fakir-miskin), seperti terkandung dalam erti ayat berikut: “...Makanlah dari
buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari
memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin), dan janganlah kamu
~ 24 ~
berlebih-lebihan...‖ (Q.S. al-An‘am: 141). Untuk menjembatani perbedaan sosio-
ekonomi antara si kaya dan si miskin, pemerintah harus melakukan usaha optimal dalam
mewujudkan keadilan sosial dengan merapatkan gap (jurang pemisah) antara si kaya dan
si miskin, diantaranya, dengan mengoptimalkan institusi zakat.
Dari penjelasan di atas, jelas terlihat bahwa pemerintah sebagai institusi yang mengatur
jalannya kehidupan bernegara diwajibkan untuk mengatur jalannya roda perekonomian
agar praktek-praktek yang bertentangan dengan nilai-nilai Islami seperti monopoli,
konsentrasi kekayaan pada golongan tertentu dan berbagai tindakan kejahatan ekonomi
lainnya seperti aksi spekulasi dapat dihindari. Selain itu, kebijakan-kebijakan ekonomi
yang dibuat pemerintah hendaklah ditujukan untuk menciptakan keseimbangan dan
sekaligus keadilan sosio-ekonomi negara.
Dalam Islam, pembahasan tentang kedudukan modal (capital) sebagai salah satu dari
faktor-faktor produksi juga mendapat perhatian khusus. Pengumpulan modal secara
besar-besaran melalui institusi keuangan ribawi baik dalam sistem ekonomi kapitalis
maupun komunis adalah bertentangan dengan fitrah manusia sebagai khalifah Allah SWT
di bumi ini. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa Islam menghalalkan hak
kepemilikan terhadap faktor-faktor produksi dan harta-benda sejauhmana proses
pemilikan, pengurusan dan pengelolaan harta benda itu mengikut ajaran Ilahiah. Berbagai
cara penumpukan harta dan akumulasi modal terpusat serta berbagai praktek untuk
meraup keuntungan secara mambabi buta tanpa peduli nilai-nilai moral seperti
memlibatkan praktek riba secara rakus, serakah dan penuh hawa-nafsu adalah cara-cara
kotor, jijik dan lagi menjijikkan yang sangat keras dilarang Islam. Larangan Islam ini,
misalnya dapat kita simak dari ayat-ayat berikut yang bermakna: ―Hai orang-orang yang
beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib
Nasrani benar-benar memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil dan mereka
menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan
emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah
kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih‖ (Q.S. at-Taubah: 34);
dan ―Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-
~ 25 ~
lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (perbelanjaan itu) di tengah-tengah antara
yang yang demikian‖ (Q.S. al-Furqan: 67).
Berdasarkan arti ayat-ayat di atas jelas kita lihat bahwa Islam sangat menggalakkan
umatnya untuk menggunakan harta benda (faktor-faktor produksi) mereka secara
sederhana dan tidak mubazir (extravagance). Hal ini diperkuat lagi dengan ayat-ayat
berikut: ―Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan
janganlah kamu terlalu menghulurkan karena itu kamu menjadi tercela dan menyesali‖
(Q.S. al-Isra‘: 29); ―Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara
syaitan...‖ (Q.S. al-Isra‘: 27); dan “...makan dan minumlah kamu, dan janganlah
berlebih-lebihan...” (Q.S. al-A‘raf: 31).
Demikian pula Rasulullah SAW cukup banyak memberi peringatan kepada umatnya agar
menggunakan harta mereka dengan berhemat cermat sebagai salah satu cara terbaik
untuk hidup sejahtera, khususnya dalam menghadapi krisis ekonomi yang terjadi di luar
jangkaan manusia. Ini dapat kita lihat dari beberapa Hadist berikut yang bermakna:
“...Rasulullah SAW pernah membeli kurma dari Bani Nadhir dan menyimpannya untuk
perbekalan setahun buat keluarga...‖ (H.R. Bukhari); ―Simpanlah sebagian dari harta-
harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu‖ (H.R.
Bukhari); dan “...saya (Rasulullah) sungguh berlindung dari kemiskinan, kelangkaan dan
kejahatan....” (H.R. Bukhari). Pendek kata, penggunaan faktor-faktor produksi (harta
benda) secara amanah mengikut nilai-nilai Ilahiah akan menjamin terwujudkan
kesejahteraan ekonomi umat yang berkeadilan dan bebas dari berbagai penyakit sosio-
ekonomi, tidak seperti dalam sistem ekonomi komunis dan kapitalis yang bebas nilai
(value-free).
Timbulnya penyakit sosio-ekonomi dalam sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, dimana
pencapaian duniawi seorang individu diukur dengan tingkat pemilikan materi (harta-
benda)—yang nyata sekali berlaku antara golongan kaya dan miskin akibat tidak adanya
pemerataan kesejahteraan ekonomi dalam negara— sebenarnya sangat bertentangan
dengan indikator kesuksesan seorang individu Muslim dalam Islam. Di sisi Allah SWT,
~ 26 ~
setiap individu Muslim adalah sama kedudukannya, walaupun memiliki perbedaan warna
kulit, suku, bangsa, kekayaan, tingkat pendidikan dan berbagai kedudukan duniawi
lainnya. Dalam Islam, "Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi
Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu" (Q.S. al-Hujarat: 13). Jadi,
bukanlah banyaknya kepemilikan harta-benda, tingginya jabatan dan banyaknya usaha
bisnis yang dimiliki dan paras rupa yang menjadi ukuran kemuliaan seseorang dalam
ajaran Islam.
Ayat al-Hujurat di atas menunjukkan bahwa ajaran Islam sangat menfokuskan
pembentukan moral Islami para pelaku ekonomi, bukannya penumpukan harta kekayaan
secara membabi buta. Itulah sebabnya sebagai agama yang hanif, universal dan syumul,
Islam telah meletakkan azas perekonomian baik menyangkut persoalan ekonomi mikro
(micro-economy), seperti larangan monopoli, menimbun harta, rakus, bernafsu dan
mengabaikan hak-hak si miskin maupun dalam masalah ekonomi makro (macro-
economy), seperti masalah zakat, peraturan pemerintah demi terciptanya kelangsungan
ekonomi yang stabil dan berkeadilan.
Islam sebagai agama yang sempurna telah menawarkan konsep ekonomi Islam sebagai
jawaban dan solusi bagi semua kelemahan yang melekat pada ke dua sistem ekonomi
kapitalis dan komunis. Kelembaban dan kemerosotan ekonomi serta krisis ekonomi yang
silih berganti melanda ekonomi dunia itu terjadi semata-mata karena kedhaifan sistem
ekonomi kapitalis dan komunis yang dikendalikan oleh hawa-nafsu. Sedangkan dalam
ekonomi Islam, semua tindakan ekonomi itu diarahkan oleh akal dan wahyu Ilahi serta
Sunnatullah, sehingga aktivitas ekonomi yang dilakukan itu akan memberikan manfaat,
bukannya mudarat baik bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat maupun bangsa dan
negara. Sebaliknya, apabila hawa-nafsu telah menguasai manusia dalam berbagai
aktivitasnya, termasuk aktivitas ekonomi, tentunya, akan semakin memperburuk moral
para pelaku ekonomi sehingga akan mengundang terjadinya krisis ekonomi silih berganti.
Bila kejahilan ekonomi ini sudah terjadi secara membudaya, maka krisis ekonomi dan
berbagai penyakit ekonomi yang merugikan umat sangat berpotensi terjadi kapan saja. Ini
semua disebabkan ketamakan dan kerakusan (greediness) manusia yang didorong oleh
~ 27 ~
hawa-nafsu untuk memperkaya diri sendiri tanpa mempedulikan dampak negatifnya
terhadap orang lain.
Sebagai khalifah Tuhan, kita harus menyadari bahwa dunia ini bukanlah milik mutlak
kita. Kita hanya sebagai pemegang amanah Allah SWT mempunyai tanggung jawab
untuk memelihara kemakmuran bumi beserta segala isinya. Karena, sesungguhnya, di
hari akhirat kelak kita akan diminta pertanggungjawapan terhadap semua yang telah kita
perbuat di dunia ini. Hal ini selaras dengan firman Allah SWT, yang berarti:
"Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang ada di bumi ini sebagai perhiasan
baginya, agar Kami menguji mereka (manusia), siapakah di antara mereka yang terbaik
perbuatannya" (Q.S. al-Kahf: 7). Dan perlu, sekali lagi, diingatkan bahwa dalam
mempertanggungjawapkan semua amalan kita di Mahkamah Ilahi di hari akhirat kelak,
kita tidak memiliki peluang untuk memberi saksi palsu, apatah lagi untuk menipu Allah
karena "Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada Kami tangan
mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka
usahakan" (Q.S. Yasin: 65).
Dari uraian di atas jelas terlihat bahwa sistem ekonomi Islam memiliki keunggulan
tersendiri yang tiada dimiliki oleh ke dua sistem ekonomi komunis dan kapitalis dalam
menyelesaikan problema ekonomi umat. Muatan nilai-nilai (values loaded) Ilahiah yang
melekat dalam ekonomi Islam telah menjadikan sistem ekonomi ini memihak
kepentingan dan kemaslahatan semua golongan masyarakat, terutama kaum ekonomi
lemah tidak seperti sistem ekonomi kapitalis yang hanya memberi keuntungan bagi
golongan kaya-raya, sedangkan golongan papa-kedana sentiasa tertindas. Begitu juga
sistem ekonomi komunis yang tidak menghargai jerih payah, skills dan bakat individu
dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan negara telah menjadikan sistem ini
jauh dari nilai-nilai keadilan. Tidak seperti ekonomi Islam yang penuh dengan nilai-nilai
samawi (Islami), ke dua sistem ekonomi kapitalis dan komunis yang ‗bebas nilai‘ ini
telah mengabaikan nilai-nilai moral, etika, dan akhlaqul karimah dalam berbagai aktivitas
ekonomi mereka. Akibatnya, berbagai kejahilan ekonomi dan krisis ekonomi silih
berganti terjadi. Berhasilkah ekonomi Islam memberi solusi terhadap berbagai penyakit
~ 28 ~
dan krisis ekonomi yang melanda umat sejagat, atau setidaknya bagi negara-negara
Muslim? Jawabannya, ada pada setiap individu Muslim. Sejauhmana mereka mampu
menterjemahkan seruan Ilahi untuk diaplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari
dengan penuh amanah dan tanggung jawab sebagai khalifatullah fil-Ard, sejauh itu pula
ekonomi Islam akan mampu memberi jawaban dan menyediakan solusi. Wallahu‟alam
bissawab.
~ 29 ~
BAB 3
MENGKRITISI TEORI PEMBANGUNAN EKONOMI
KONVENSIONAL
Sejak ilmu ekonomi mendapat pengakuan sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri sekitar
abad ke-17 Masehi, para pemikir ekonomi barat telah menggunakan metode yang keliru
untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dunia, yang biasanya diukur dari pertumbuhan
GNP (Gross National Product) atau pendapatan per-kapita (income per-capita). Mereka,
pada awal-awal kemunculan teori pembangunan ekonomi, sempat menafikan peran ilmu
pengetahuan sebagai salah satu indikator penting dalam teori ekonomi untuk mengukur
pembangunan ekonomi sebuah negara. Pengabaian ini telah menyebabkan mereka gagal
total untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pembangunan ekonomi baik
perbedaan pembangunan ekonomi yang terjadi dalam sebuah negara antar waktu maupun
perbedaan pembangunan ekonomi yang terjadi antar negara. Mereka lupa bahwa sejak
lebih 1.400 tahun yang silam, Islam telah menegaskan bahwa, di samping rahmat Allah
swt, ilmu pengetahuan merupakan salah satu faktor terpenting bagi manusia untuk
mewujudkan kesejahteraan (pembangunan ekonomi) dan kemenangan (falah) di dunia
dan akhirat. Bukti ini cukup jelas direkamkan Allah swt dalam al-Qur'an, Surah yang
pertama sekali diturunkan di Gua Hira' kepada kekasihNya Muhammad saw, yaitu surat
al-Alaq yang intinya menyerukan umat untuk membaca (mencari ilmu).
Tulisan ini meninjau dan menguak kedhaifan teori pertumbuhan ekonomi barat, sejak
teori itu pertama kali digagaskan. Walaupun pada awalnya para ahli ekonomi barat
sempat mengabaikan peran ilmu pengetahuan sebagai salah satu indikator penting dalam
pembangunan ekonomi, namun di akhir milineum ke-II mereka telah menyadari bahwa
penguasaan ilmu pengetahuan adalah mutlak diperlukan untuk membangun ekonomi
negara. Ini, secara jelas, menunjukkan bahwa, akhirnya, para ahli ekonomi barat terpaksa
mengakui kebenaran kata-kata Allah swt yang telah dituangkan dalam kitab suci umat
Islam, al-Qur'an tentang pentingnya peran ilmu pengetahuan dalam menjalani kehidupan
di dunia fana ini.
~ 30 ~
Metode yang Keliru
Pada awal kelahirannya, teori-teori ekonomi pembangunan konvensional telah
mengabaikan peran penting ilmu pengetahuan sebagai salah satu faktor utama penyebab
terjadinya pembangunan ekonomi umat. Sebagai penggagas teori pembangunan ekonomi,
Harrod, R.F (1939) dalam artikelnya "An Essay in Dynamic Theory" yang dipublikasikan
dalam Economic Journal telah mengabaikan peran ilmu pengetahuan dalam teori
pertumbuhan ekonominya. Hal yang sama juga dapat kita jumpai dalam tulisan Evsey
Domar (1946) dengan judul "Capital Expansion, Rate of Growth, and Employment" yang
dipublikasikan dalam Jurnal Econometrica. Teori-teori mereka, yang kemudian, dikenal
dengan teori pertumbuhan ekonomi ―Harrod-Domar‖ hanya melihat jumlah tabungan dan
modal per-output (saving and capital per output) sebagai dua faktor penting dalam
pertumbuhan ekonomi. Begitu juga Robert Solow (1956) dalam tulisannya "A
Contribution to the Theory of Economic Growth" yang diterbitkan dalam Quarterly
Journal of Economics menegaskan bahwa jumlah tabungan dan penduduk adalah dua
faktor utama penyebab berlakunya pertumbuhan ekonomi. Dalam tulisannya, Solow
berkesimpulan bahwa semakin tinggi tingkat tabungan sesebuah negara maka akan
semakin maju negara tersebut. Sebaliknya, semakin banyak jumlah penduduk sesebuah
negara, maka semakin miskin negara itu.
Bila sekilas-lintas merujuk pada teori-teori pembangunan ekonomi di atas dan kaitannya
dengan realitas sekarang, maka teori mereka tersebut jelas berada jauh dari nilai-nilai
kebenaran. Hanya negara Indonesia sajalah yang memiliki jumlah penduduk nomor
empat terbesar di dunia, pertumbuhan ekonominya lemah. Sedangkan negara-negara
Cina, Amerika Serikat, India, dan Russia bisa dikatakan memiliki pertumbuhan ekonomi
yang stabil. Di samping itu, teori mereka baik teori Harrod-Domar maupun teori Solow
jelas tidak mampu atau gagal mengukur perbedaan pertumbuhan dalam sebuah negara
dari masa ke masa dan perbedaan pertumbuhan ekonomi yang berlaku antar negara.
Dengan kata lain, untuk mengukur pertumbuhan ekonomi tidaklah memadai dengan
hanya mengukur pertumbuhan modal fisik dan jumlah penduduk (tenaga kerja) semata,
pasti ada faktor lain, yang telah terabaikan, yang sangat menentukan pertumbuhan
ekonomi negara.
~ 31 ~
Perangkap (Trap) Teori Ekonomi Pembangunan Barat
Kalau kita lebih bijaksana melihat implikasi teori pertumbuhan ekonomi di atas, secara
implisit, para ahli ekonomi barat jelas telah menjebak negara-nagara Muslim yang
mayoritas kurang memiliki modal yang memadai untuk membangun ekonomi negaranya,
agar berhutang pada negara maju. Niat jahat negara maju untuk mengelabui negara
miskin jelas terlihat dari beberapa hasil kajian ilmiah yang dilakukan para ahli ekonomi
barat di negara-negara miskin yang menemukan bahwa kemunduran negara-negara
miskin adalah mutlak disebabkan oleh kekurangan modal yang mereka miliki. Sehingga
dalam membangun ekonomi negara, mereka merekomendasikan kepada negara-negara
miskin agar mendapatkan modal yang memadai, tentunya, dengan berhutang pada
negara-negara maju. Inilah jebakan negara-negara maju agar mereka dapat dengan
leluasa ikut campur tangan untuk mengatur perekonomian negara-negara miskin, yang
umumnya, didiami oleh mayoritas umat Islam.
Perlu kita sadari bahwa kalaulah negara-negara Muslim telah membiayai pembangunan
ekonomi mereka dengan bermodalkan hutang dari negara-negara maju, maka secara tidak
langsung kita telah dengan sengaja mengundang campur tangan negara asing untuk
mengatur kebijakan pembangunan ekonomi negara kita. Karena diakui atau tidak, bila
pembangunan ekonomi negara telah ditopang dengan hutang luar negeri, maka di sinilah
punca kehinaan bangsa kita bermula. Barangkali, atas kesadaran inilah, Mantan Perdana
Menteri Malaysia, Mahathir Mohammad berani menolak sekeras-kerasnya ―bantuan‖
(pinjaman) asing untuk membiayai pembangunan ekonomi negaranya. Mahathir dan
rakyat Malaysia tidak mau membangun negerinya dengan dana dari berhutang pada
negara asing, walau dalam menghadapi krisis ekonomi sekalipun. Pengaruh negatif
membiayai pembangunan negara dengan berhutang pada negara lain dapat kita saksikan
di Indonesia, sampai akhir 2002 pun masih kucar-kacir membebaskan perekonomiannya
dari pengaruh campur tangan negara-negara asing.
Setelah mengidentifikasi jebakan para ahli ekonomi barat melalui teori pertumbuhan
ekonominya, seperti dijelaskan di atas, maka sudah seharusnya umat Islam bertindak
lebih hati-hati dalam mengatur kebijakan pembangunan ekonomi negara dengan berusaha
semaksimal mungkin untuk tidak membiayai pembangunan ekonomi yang bersumber
~ 32 ~
dari hutang negara-negara maju. Dalam konteks ini, mungkin, tindakan Mantan Perdana
Menteri Malaysia, Mahathir Mohammad dalam menentang sekeras-kerasnya usaha
untuk membiayai pembangunan ekonomi Malaysia yang bersumber dari hutang luar
negeri haruslah dijadikan contoh teladan oleh negara-negara Muslim lainnya, terutama
negara Indonesia yang ekonominya dalam keadaan sekarat tercekik oleh hutang.
Kalaupun negara-negara Muslim terpaksa berhutang, hendaklah hutang itu dipinjami dari
sumber-sumber yang bebas riba, dan untuk itu, alternatif wadah Dana Moneter Islam
Internasional (Islamic International Monetary Funds, IIMF) menjadi solusi yang tepat.
Negara-negara Muslim di dunia dihimbau sebaiknya segera menyelenggarakan
Konferensi Internasional untuk membahas agenda penyelesaian krisis moneter melalui
pembentukan lembaga bersama IIMF yang berfungsi sebagai institusi peminjam modal
yang bebas riba.
Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Ekonomi Umat
Selanjutnya, kegagalan teori pembangunan Harrod-Domar dan Solow dalam
mengidentifikasi indikator penting penyebab berlakunya pembangunan ekonomi dunia
telah dikritik oleh Mankiw, Romer, dan Weil (1992) dalam artikelnya, "A Contribution to
the Empirics of Economic Growth" yang dipublikasikan dalam Quarterly Journal of
Economics dengan mengatakan bahwa sungguh dhaif dan sangat tidak realistik asumsi-
asumsi teori pertumbuhan ekonomi terdahulu, seperti asumsi hanya satu barang tersedia
dalam negara, mengabaikan peran pemerintah, pertumbuhan tenaga kerja, depresiasi, dan
perkembangan teknologi. Untuk merevisi kelemahan teori terdahulu, mereka telah
memasukkan teknologi dan modal manusia (human capital) di samping modal fisik
(physical capital) sebagai faktor penting penentu pembangunan ekonomi dalam teori
pertumbuhan ekonomi baru mereka. Modal manusia, menurut mereka, termasuklah
pendidikan keahlian buruh, kekuatan hak kepemilikan, kualitas infrastruktur, dan sikap
budaya terhadap entrepreneurship dan kerja. Teori mereka ini, kemudian, dikenal dengan
teori "Beyond Solow" yang telah memperkenalkan ilmu pengetahuan sebagai salah satu
faktor penting penyebab terjadinya pembangunan ekonomi negara di samping faktor
modal fisik, buruh, dan teknologi.
~ 33 ~
Karena kebingungan mereka atas kelemahan teori pertumbuhan ekonomi terdahulu, maka
dalam teori "Beyond Solow" ini mereka juga telah memasukkan Riset dan Pengembangan
(Research and Development, R&D) atau ilmu pengetahuan sebagai faktor penting
penentu pembangunan ekonomi sesebuah negara. Alasan kenapa mereka memasukkan
ilmu pengetahuan sebagai salah satu faktor penting penentu pembangunan ekonomi,
seperti dikatakan oleh David Romer (1996) dalam bukunya "Advanced Macroeconomics"
bahwa ilmu pengetahuan adalah sangat berguna untuk menghasilkan ilmu pengetahuan
yang baru sebagai faktor utama penentu pembangunan ekonomi negara. Karena tatkala
proses akumulasi ilmu pengetahuan dimulai, ekonomi akan bergerak ke arah
pertumbuhan yang berkelanjutan. Mereka juga mengakui bahwa ilmu pengetahuan adalah
bersifat ―non-rival‖ dimana penggunaan sebagian ilmu pengetahuan pada waktu dan
untuk kegunaan tertentu oleh seseorang tidak akan menghalang orang lain untuk
menggunakan ilmu pengetahuan yang sama. Begitu juga J. M. Clark (2000), seorang ahli
ekonomi Kapitalis telah mengakui bahwa "ilmu pengetahuan adalah satu-satunya faktor
produksi yang tidak pernah berkurang (non-deminishing return)". Ini menunjukkan
bahwa satu-satunya benda di dunia ini yang tidak akan pernah berkurang baik dari segi
kuantitas maupun kualitas walaupun ia telah digunakan berulang-kali adalah ilmu
pengetahuan. Apa yang dikatakan mereka, sebenarnya, lebih 14 abad yang lampau telah
ditegaskan oleh Ali bin Abi Talib r.a., Khulafa ar-Rasyidin yang terakhir bahwa satu-
satunya benda yang bila diberikan pada orang lain tidak pernah berkurang, malah ia
senantiasa bertambah, tidak ada lain kecuali ilmu pengetahuan.
Dengan dimasukkannya ilmu pengetahuan (teknologi) sebagai salah satu faktor penting
untuk mengukur pembangunan ekonomi negara, maka perbedaan pertumbuhan ekonomi
dalam sebuah negara dari masa ke masa kini telah berhasil diukur. Perkembangan ilmu
pengetahuan didapati sebagai penyebab utama kenapa standar hidup dan pertumbuhan
ekonomi negara jauh lebih baik pada masa sekarang dibandingkan dengan masa silam.
Namun, sekali lagi, mereka masih gagal mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya
perbedaan pertumbuhan ekonomi antar negara. Hal ini telah dibuktikan oleh Denison
(1985) dalam bukunya ―Trends in American Economic Growth: 1929-1982‖, yang
menemukan bahwa menurunnya pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat pada periode
~ 34 ~
1929-1982 adalah disebabkan oleh melemahnya keahlian buruh, naiknya harga minyak,
dan akibat kekakuan peraturan pemerintah (the rigidity of goverment rules). Selanjutnya,
Yong (1994) dalam artikelnya "The Tiranny of Numbers: Confronting the Statistical
Reality of the East Asian Growth Experience" yang dipublikasikan dalam Quarterly
Journal of Economics, mendapati bahwa penyebab utama meningkatnya pertumbuhan
ekonomi negara-negara Hong Kong, Singapura, dan Korea Selatan adalah disebabkan
oleh naiknya tingkat investasi asing, meningkatnya peran aktif dan produktivitas buruh
dalam pembangunan ekonomi. Singkatnya, bukti empiris ini jelas telah menafikan bahwa
perbedaan pertumbuhan ekonomi antar negara adalah terjadi akibat perbedaan
pemilikan/penguasaan teknologi antar negara.
Alasan lain kenapa perbedaan pembangunan ekonomi antar negara berlaku bukan akibat
perbedaan pemilikan teknologi adalah disebabkan oleh sifat teknologi itu sendiri yang
dapat dipindahkan (transferable) dari satu tempat (negara) ke tempat lain. Negara-negara
miskin yang tidak memiliki teknologi terkini, tentunya, dapat mendatangkannya dari
negara-negara maju. Walaupun secara teoritis demikian, namun realitas menunjukkan
bahwa negara miskin tetap miskin dan bahkan menjadi lebih papa, sementara itu negara
maju semakin maju. Realitas ini telah mendorong para ahli ekonomi barat untuk memeras
otaknya kembali mencari jawaban yang sesungguhnya apa penyebab terjadinya
perbedaan pertumbuhan ekonomi antar negara.
Rahmat Ilahi dan Pembangunan Ekonomi Umat
Setelah melakukan riset lanjutan, Mankiw, Romer, dan Weil (1992) dan Romer (1996)
barulah menemukan jawaban yang hampir pasti kenapa pertumbuhan ekonomi antar
negara berbeda. Mereka berkesimpulan bahwa tarjadinya perbedaan pertumbuhan
ekonomi antar negara maju dengan negara miskin bukanlah disebabkan oleh ketidak ada
upayaan negara miskin untuk mengakses teknologi dari negara maju, tetapi semata-mata
disebabkan oleh kebodohan orang-orang (human capital incapability) yang berdomisili di
negara-negara miskin untuk menggunakan teknologi. Dalam risetnya, mereka
menemukan bahwa 80% perbedaan pertumbuhan ekonomi antar negara adalah
~ 35 ~
disebabkan oleh faktor modal fisik dan faktor modal manusia. Sedangkan, 20% lagi
sisanya mereka kategorikan ke dalam faktor-faktor yang tidak dapat diidentifikasi
(diukur), yang dalam istilah mereka disebut dengan ―residual‖ (nilai sisa). Menurut
Abramovitz (1956) and Denison (1967), sebenarnya, residual ini adalah pertanda atau
bukti yang menunjukkan kedhaifan dan kebodohan mereka dalam mengukur perbedaan
pertumbuhan ekonomi antar negara. Mereka lupa bahwa faktor rahmat Allah swt, di
samping ilmu pengetahuan untuk menguasai teknologi adalah merupakan faktor yang
sangat penting dalam pembangunan ekonomi umat. Karena tanpa limpahan rahmat Allah
swt, maka sangatlah susah dan bahkan mustahil bagi kita untuk dapat membangun
ekonomi negara. Sebagai contoh rahmat Allah swt adalah rahmat hujan. Bila hujan tidak
pernah turun, mana mungkin para petani mampu menghasilkan panen yang banyak, yang
pada gilirannya, akan meningkatkan jumlah komoditas hasil pertanian yang beredar di
pasar sehingga berlakulah pembangunan ekonomi.
Atas pertimbangan inilah Ramzan Akhtar (1993) terpanggil untuk melakukan riset
lanjutan. Dalam artikelnya "Modelling the Economic Growth of An Islamic Economy"
yang diterbitkan dalam ―The American Journal of Islamic Social Science (AJISS)‖,
Akhtar mengkritik sekeras-kerasnya teori pertumbuhan ekonomi barat. Akhtar
menegaskan bahwa tanpa adanya rahmat Allah swt, maka pembangunan ekonomi
sangatlah mustahil untuk berlaku. Kenapa para ahli ekonomi barat tidak memasukkan
rahmat Allah swt sebagai faktor penting penyebab terjadinya pembangunan ekonomi
negara dalam teori mereka adalah semata-mata disebabkan oleh kejahilan dan
ketidakpercayaan mereka terhadap kekuasaan Allah swt. Dengan alasan karena Allah swt
itu bersifat abstrak, dan ianya tidak dapat dibuktikan secara empiris, maka mereka tidak
mempercayainya. Sungguh mereka lupa bahwa mereka dilahirkan ke dunia ini seolah-
olah lahir begitu saja tanpa ada sesiapapun yang mentakdirkannya.
Singkatnya, perbedaan penguasaan ilmu pengetahuan untuk mengoperasikan mesin-
mesin teknologi dan rahmat Allah swt adalah penyebab utama berbedanya pertumbuhan
ekonomi antar negara. Penguasaan ilmu pengetahuan dan rahmat Allah swt merupakan
“driving force‖ pertumbuhan ekonomi negara. Oleh karena itu, terbatasnya keahlian dan
~ 36 ~
ilmu pengetahuan negara-negara miskin untuk mengoperasikan mesin-mesin
berteknologi tinggi dan teknologi komunikasi dan informasi (Information,
Communication and Technology, ICT) adalah merupakan faktor utama penyebab negara
miskin terus teperangkap dalam kemiskinan, sementara itu negara maju terus
mempergunakan kelemahan negara-negara miskin untuk memperkaya diri mereka. Sudah
masanya umat Islam harus menguasai semua bidang kehidupan, karena bukanlah perkara
mudah untuk membangun ekonomi secara komprehensif, adil, dan berkelanjutan
(sustainable) tanpa memiliki kemampuan untuk mengoperasikan dan bahkan menguasai
mesin-mesin teknologi canggih. Hal ini sangatlah tepat seperti apa yang telah dikatakan
oleh Robert Lucas (1988) dalam artikelnya berjudul "On Mechanics of Economics
Developmnent" yang diterbitkan dalam Journal of Monetary Policy sebagai berikut:
"sekali kita mulai berpikir tentang pembangunan ekonomi, maka sangatlah susah dan
tidak mempunyai masa untuk memikirkan tentang perkara-perkara yang lain".
Dari penjelasan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa kegagalan para ahli ekonomi
barat untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan pertumbuhan
ekonomi dalam sebuah negara dari masa ke masa dan perbedaan pertumbuhan ekonomi
antar negara adalah mutlak disebabkan oleh kedhaifan dan kejahilan mereka sendiri.
Selain sempat mengabaikan peran ilmu pengetahuan pada awal-awal kemunculan teori
pembangunan ekonomi, hingga detik ini mereka masih menafikan kehadiran rahmat
Allah swt sebagai faktor terpenting penyebab berlakunya pembangunan ekonomi umat.
Karena tingginya nilai ilmu pengetahuan dalam Islam, maka penguasaan ilmu
pengetahuan secara komprehensif dan benar jelas akan memudahkan umat Islam untuk
membangun ekonominya. Namun, pembangunan ekonomi umat tidak akan pernah
berlaku tanpa mendapat restu Allah swt melalui cucuran rahmatNya
~ 37 ~
BAB 4
MEMILIH BARANG DAN JASA DALAM EKONOMI ISLAM
Hampir semua pakar ekonomi setuju bahwa ekonomi sering didefinisikan sebagai suatu
ilmu atau seni bagaimana seseorang melakukan pemilihan (choices) terhadap sesuatu
barang atau jasa dengan cara mengalokasikan sumber daya alam yang terbatas (limited)
atau langka (scare) secara efisien. Karena rumitnya proses pemilihan ini, maka peran
ilmu pengetahuan adalah mutlak diperlukan. Sebab tanpa memiliki ilmu pengetahuan
yang memadai terhadap barang dan jasa yang akan dibeli, keputusan yang diambil
cenderung akan tidak memaksimumkan kepuasan para pembeli. Biasanya, hal ini
disebabkan oleh tindakan spekulasi atau tindakan yang bersifat terkaan (guesswork)
terhadap barang dan jasa yang dipilih. Artinya bahwa sebuah proses pemilihan tanpa
didasari dengan pemahaman ilmu pengetuan yang memadai tidaklah dapat dikategorikan
sebagai suatu cara yang tepat dalam menjatuhkan pilihan terhadap barang dan jasa yang
ingin dibeli.
Dalam setiap proses pemilihan dalam ekonomi, kita hanya memiliki satu kesempatan saja
untuk menetapkan pilihan. Dan pilihan yang kita buat tersebut juga tidak terlepas dari dua
kemungkinan pilihan, yaitu memilih barang dan jasa secara tepat atau sebaliknya,
menetapkan pilihan yang salah. Kedua alternatif ini, dalam ilmu ekonomi sering disebut
dengan proses ―tolak angsur‖ (trade off). Dalam kaitannya dengan konsep pemilihan
barang secara Islami, contoh trade-off ini dapat dilihat bahwa ketika kita telah
menjatuhkan pilihan untuk membeli barang dan jasa yang halal, maka kecendrungan
untuk memilih barang dan jasa yang haram sudah tertutup. Jadi, untuk menetapkan
pilihan yang tepat, maka keputusan yang dibuat itu haruslah didahului dengan observasi
pasar yang menyeluruh dan studi tentang barang dan jasa serta tingkah laku pasar secara
teliti.
Tidak seperti halnya ilmu ekonomi Islam, ilmu ekonomi konvensional hanya merupakan
suatu ilmu tentang cara bagaimana pemilihan terhadap barang dan jasa itu dibuat oleh
~ 38 ~
para pelaku ekonomi. Dalam melakukan investasi misalnya, pemilihan saham atau
obligasi untuk dibeli hanya semata-mata didasari atas orientasi keuntungan maksimum
(maximum profit oriented). Begitu juga dengan pembelian rumah dan mobil biasanya
dibuat hanya berdasarkan harga, kualitas dan kenyamanan dari barang-barang tersebut.
Hal ini menjelaskan bahwa ilmu ekonomi konvensional sangat jarang melihat
sejauhmana pengaruh pembelian sesuatu barang terhadap kesejahteraan hidup orang lain.
Hal inilah yang membuat ilmu ekonomi konvensional akhir-akhir ini hanya berfungsi
tidak lebih sebagai suatu ilmu yang berkaitan dengan proses pemilihan barang dan jasa
saja. Sedangkan pengaruh dari pemilihan sesuatu barang dan jasa terhadap kesejahteraan
orang lain lebih cenderung dikategorikan sebagai persoalan etika (akhlaq) yang
pembahasannya adalah di luar dari tanggung jawab ilmu ekonomi.
Dalam proses pemilihan terhadap barang dan jasa, ilmu ekonomi konvensional hanya
didasarkan pada kemampuan akal (reasons) dan fakta-fakta (facts) semata. Walaupun
demikian, dalam prakteknya sangat jarang kita temui kedua faktor ini difungsikan secara
maksimal dan berimbang dalam proses pemilihan. Hal ini dapat kita lihat dalam buku-
buku teks ekonomi yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan. Ilmu ekonomi
konvensional secara terang-terangan telah mengabaikan aspek tingkah laku psikologi
kemanusiaan (human psychological behaviuor) dalam proses pemilihan sehingga
menyebabkan barang dan jasa yang dipilih tidak tepat dan terarah sesuai dengan
keinginan mereka. Pemilihan barang dan jasa yang tidak tepat dan sembrono akan
memberi dampak negatif terhadap ekonomi secara makro. Pengaruh makro ini dapat kita
lihat dari pengaruh pembelian sesuatu barang tertentu terhadap kenaikan tingkat inflasi
atau penurunan daya beli masyarakat, kekurangan makanan, pengangguran,
ketidakstabilan mata uang, maupun terhadap kemunduran pertumbuhan ekonomi, dan
berbagai penyakit ekonomi lainnya.
Sementara itu, dalam Islam, studi terhadap pemilihan barang dan jasa sangat jelas
diungkapkan oleh Imam al-Ghazali dalam Ihya Ulum al-Din, ketika membahas bab etika
(akhlaq). Dengan merujuk pada pendapat Imam al-Ghazali, Dr. Saiful Azhar Roesly
~ 39 ~
(2000) menyebutkan bahwa proses pemilihan barang dan jasa dalam Islam itu meliputi
lima tahap penting. Pertama, ide (al-khawarij). Ide ini menurut Imam al-Ghazali adalah
merupakan dasar utama (fountainhead) daripada semua tindakan manusia. Ide ini akan
mempengaruhi hati manusia baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal.
Ide ini ada yang bersifat konstruktif dan destruktif. Ide yang bersifat konstruktif selalu
mengarah manusia kepada suatu tindakan yang baik, sedangkan ide yang bersifat
destruktif senantiasa bermuara pada sebuah kejahatan. Ide konstruktif biasanya
bersumber dari inspirasi atau intuisi (ilham), sedangkan yang bersifat destruktif biasanya
bersumber dari bisikan syaitan (waswas).
Merujuk pada keterangan di atas, maka dapat kita fahami bahwa jika pemilihan terhadap
sesuatu barang dan jasa yang sifatnya lebih menguntungkan kepentingan individu (self-
interest) dengan mengabaikan kepentingan umum (public interest), maka dapat dipastikan
bahwa keputusan pemilihan itu didorong oleh ide destruktif yang bersumber dari hasil
bisikan syaitan. Praktek-praktek ini sangat mudah kita jumpai dalam sebuah perusahaan
dimana apabila terjadinya pertentangan antara dua kepentingan, yaitu kepentingan para
pemegang saham (shareholders) dan kepentingan perusahaan (management) itu sendiri.
Dalam menghadapi problema ini biasanya para pemegang saham akan terdorong untuk
mengeluarkan biaya semaksimal mungkin untuk memonitor tingkah laku para manager
sehingga tidak mejalankan operasional perusahaan melenceng dari tujuan yang telah
ditetapkan.
Seperti disebutkan sebelumnya bahwa ide yang baik atau ilham ini bersumber dari akal
yang mendapat bimbingan hidayah Allah swt (al-taufiq). Ketika ide itu bersemi dalam
hati seseorang, maka ia akan menjadi pendorong (impulse) sehingga timbullah
kecenderungan (al-raghba) untuk memilih sesuatu barang atau jasa sebagai tahap kedua.
Kecenderungan ini akan berlanjut melalui proses intelektual yang dapat menumbuhkan
sebuah keyakinan (al-‗itiqad) bahwa ide itu adalah merupakan suatu ide yang baik.
Setelah adanya keyakinan diri (tahap ketiga), maka timbullah suatu keinginan (al-iradah)
dalam diri seseorang untuk segera memiliki barang dan jasa sebagai tahap keempat.
~ 40 ~
Selanjutnya, keinginan ini mendorong manusia untuk membuat suatu pemilihan yang
pada gilirannya berakhir pada sebuah usaha atau tindakan (al-ikhtiyar) untuk segera
memilih barang dan jasa yang ia kehendaki sebagai tahap terakhir.
Dari kata ikhtiyar di atas yang mendefinisikan konsep pemilihan dalam Islam, dapat
dipastikan bahwa proses pemilihan dalam Islam adalah suatu proses yang baik (khiyar)
dan membuahkan hasil pilihan yang baik pula. Jadi, setiap Muslim yang membuat
pemilihan terhadap barang dan jasa, maka sudah pasti pilihannya itu adalah pilihan yang
senantiasa berdasarkan ilmu pengetahuan dan bukan kejahilan. Dengan kata lain,
pemilihan yang dibuat tanpa berbekalkan ilmu pengetahuan sudah tentu bukan
merupakan pemilihan yang Islami tetapi lebih kepada suatu tindakan kejahilan yang
dapat merusakkan sendi-sendi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dalam Islam bukan hanya terdiri dari akal (reason)
semata, tetapi wahyu Allah swt (al-Qur‘an) dan Hadist Rasulullah saw juga sangat
memainkan peran penting dalam proses pemilihan. Sedangkan dalam ilmu ekonomi
konvensional, mereka tidak pernah percaya sama sekali terhadap keberadaan wahyu
Allah. Sebab wahyu itu, menurut mereka, tidak dapat dibuktikan secara empiris
(empirically untested). Sungguh menyedihkan, gejala tidak mempercayai pada sesuatu
makhluk/benda yang sifatnya ―ghaib‖, seperti keberadaan Allah swt dan para Malaikat,
kini secara gradual mulai merambah dunia intelektual Muslim. Tidak jarang kita melihat
bila ada sebuah riset ilmiah yang dalam presentasinya menggunakan metodologi atau
model metematik dan ekonometrik yang rumit (complicated), maka hasil penelitian
ilmiah itu akan sangat diyakini kebenarannya ketimbang dengan hasil riset yang
pembuktiannya hanya merujuk pada ayat-ayat al-Qur‘an dan Hadist Rasulullah saw.
Pendek kata, validitas, signifikan, representatif dan reliablenya hasil riset ilmiah dewasa
ini sangat ditentukan oleh tingkat kerumitan model yang digunakan, bukannya dalil naqli.
~ 41 ~
Selanjutnya, dalam Islam, pemilihan dengan menggunakan akal yang didasari atas al-
Qur‘an dan Hadist, pada gilirannya, akan menjamin kepentingan dan kemaslahatan
masyarakat secara umum. Sebagai contoh, di antara problema-problema ekonomi adalah
―apa yang harus kita produksikan dan berapa banyak‖? Untuk menjawab pertanyaan
pertama, ―apa yang harus kita produksikan‖, maka dengan merujuk pada konsep halal
dan haram berdasarkan al-Qur‘an dan Hadist, kita dengan mudah dapat memutuskan
barang-barang dan jasa-jasa apa yang halal dan haram diproduksikan dalam Islam.
Sedangkan pertanyaan kedua ―berapa banyak yang harus kita produksikan‖, ini akan
ditentukan oleh teori ekonomi dan prinsip-prinsip etika. Teori permintaan dan penawaran
(demand and supply theories) dalam ekonomi akan membantu kita dalam memutuskan
jumlah produksi terhadap sesuatu barang atau jasa jika harga barang itu naik atau turun.
Atau dengan kata lain, sejauhmana pengaruh elastisitas harga terhadap penawaran dan
permintaan barang dan jasa di pasar? Semua informasi ini sangat membantu kita untuk
menentukan berapa jumlah barang dan jasa yang sebaiknya diproduksikan.
Di samping itu, Ilmu ekonomi juga membantu kita untuk memproduksi atau
mengkonsumsi kombinasi barang atau jasa yang dapat memenuhi kepuasan maksimal
seseorang. Walaupun demikian, ilmu ekonomi itu sangat lemah dalam mengatur masalah
kesejahteraan umat (welfare of society). Untuk mengatasi kelemahan ini, maka ilmu
ekonomi harus dilengkapi dengan prinsip-prinsip etika (akhlaq). Karena dengan berpandu
pada prinsip-prinsip etika inilah, seseorang akan terhindari dari membuat pemilihan
terhadap sesuatu barang dan jasa yang hanya menguntungkan pribadinya sendiri tanpa
mempedulikan kepentingan dan kemaslahatan orang lain. Dan bila hal ini terjadi,
pemilihan yang hanya menguntungkan individu tertentu, maka pemilihan ini bukanlah
pemilihan yang Islami karena ianya tidak dilakukan melalui proses pemilihan yang
Islami.
~ 42 ~
BAB 5
MEKANISME PASAR DAN TEORI HARGA
DALAM PERSPEKTIF ISLAM
Dapat dimaklumi bahwa bila para ekonom kontemporer barat tidak menyadari apalagi
untuk memberi sebuah pengakuan bahwa keberadaan teori ekonomi konvensional
sekarang ini tidak terlepas dari teori ekonomi yang pernah dikemukakan oleh para
pemikir Islam sejak abad ke-7 Masehi. Usaha ini adalah sangat erat kaitannya dengan
usaha para intelektual barat untuk mengetepikan dan bahkan mengeliminir sumbangsih
para pemikir Islam terhadap teori-teori ekonomi modern. Namun, suatu keanehan bila
para ekonom kontemporer Islam sendiri tidak menyadari bahwa kebanyakan dari teori-
teori ekonomi konvensional sekarang adalah merupakan hasil jiplakan atau manipulasi
dari teori-teori ekonomi yang pernah diperkenalkan oleh para tokoh pemikir Islam
dahulu.
Penafian akan keberadaan teori ekonomi Islam oleh para ekonom kontemporer barat,
sebagai contoh, dapat kita lihat dari statemen yang dikemukan oleh seorang tokoh
pemikir ekonomi barat, Schumpeter (1972) terhadap konsep mekanisme pasar dan teori
harga dalam bukunya ―History of Economic Analysis‖ yang mengatakan bahwa: "as
regards the theory of mechanism of pricing, nothing worth mentioning existed before the
middle of the eighteenth century" (kaitannya dengan teori mekanisme harga, tidak ada
sesuatu yang bernilai untuk disebutkan sebelum pertengahan abad ke-18 Masehi).
Padahal bila Schumpeter mau jujur dan tidak hipokrit (hypocrite), maka dia harus
mengakui bahwa jauh sebelum pertengahan abad ke-18 M, sebenarnya, teori mekanisme
pasar dan teori harga telah sangat intens didiskusikan oleh para pemikir Islam.
Kekayaan khazanah teori ekonomi Islam yang telah dibahas oleh para tokoh pemikir dan
ulama Islam jauh sebelum teori ekonomi barat diakui sebagai suatu disiplin ilmu
tersendiri akan dibahas dalam tulisan ini. Di samping itu, tulisan ini juga bertujuan untuk
meluruskan mispersepsi umat Islam tentang eksistensi teori ekonomi pada umumnya dan
teori mekanisme pasar dan teori harga pada khususnya. Kita harus tahu bahwa teori
~ 43 ~
ekonomi yang dibangga-banggakan para ekonom kontemporer barat sekarang,
sebenarnya adalah merupakan teori ekonomi yang pernah dikemukakan oleh para pemikir
Islam dahulu. Tulisan ini juga ingin membantah statemen Schumpeter di atas dengan
menganalisa konsep mekanisme pasar dan teori harga dalam literatur ekonomi Islam
dengan pendekatan historis. Dalam analisanya, tulisan ini hanya memfokuskan
diskusinya terhadap ke-empat karya pemikir dan ulama Islam terkenal, yaitu; Kitab al-
Kharaj, karya Abu Yusuf (731- 98), Ihya Ulum al-Din-nya Imam al-Ghazali (1058-1111),
al-Hisbah dan al-Siyasah al-Syari'ah, karangan Ibn Taymiyah (1236-1328), dan Kitab al-
Muqaddimah-nya Ibn Khaldun (1332-1404).
Abu Yusuf (731- 798)
Abu Yusuf adalah seorang Chief of Justice (setingkat dengan Mahkamah Agung atau
Menteri Kehakiman) pada masa khalifah Harun ar-Rasyid. Salah satu buku beliau yang
sangat terkenal dan erat kaitannya dengan ilmu ekonomi adalah Kitab al-Kharaj (Sistem
Pajak dalam Islam). Di dalam Kitabnya itu, kita dapat menemui bagaimana pendapat
beliau tentang teori harga dalam ekonomi Islam. Menurut beliau: "Tidak ada batasan
tertentu untuk menentukan murah atau mahalnya sesuatu barang. Penentuan harga ini,
sebenarnya merupakan persoalan yang ditentukan dari langit (Allah swt) yang prinsip-
prinsipnya di luar jangkauan manusia. Harga murah bukan dikarenakan kelebihan
(surplus) barang dan jasa, dan harga mahal juga bukan disebabkan oleh kelangkaan
(scarcity) barang dan jasa yang beredar di pasar. Ini semua sangat tergantung pada
keputusan, ketetapan dan perintah Allah swt. Sebab, kadangkala, barang dan jasa yang
tersedia di pasar adalah melimpah ruah, namun harganya cukup mahal. Begitu juga
sebaliknya, harga barang dan jasa cukup murah padahal barang dan jasa tersebut sangat
terbatas jumlahnya dijual di pasar".
Berdasarkan pendapat di atas, maka kita dapat melihat bahwa selain mengakui kekuasaan
Tuhan dalam proses penentuan harga, beliau juga mengakui bahwa penentuan harga itu
tidak hanya bergantung pada faktor penawaran (supply) semata, namun juga dipengaruhi
oleh faktor permintaan (demand). Karena banyak atau sedikitnya penawaran terhadap
~ 44 ~
suatu barang dan jasa tidak akan mempengaruhi harga bila tidak adanya permintaan dari
masyarakat terhadap barang dan jasa tersebut. Ini berarti bahwa harga sesuatu barang
adalah ditentukan oleh kekuatan faktor supply dan demand. Bila demand terhadap
sesuatu barang dan jasa lebih tinggi dari supply (jumlah produksi) yang tersedia di pasar,
maka harga barang dan jasa tersebut akan menjadi lebih mahal, dan sebaliknya.
Bila kita komparasikan teori harga ekonomi konvensional dengan teori harganya Abu
Yusuf, maka jelas bahwa teori penentuan harga Abu Yusuf ini secara aklamasi telah
diakui dan diadopsi oleh para pakar ekonomi modern sekarang. Pentingnya peran kedua
faktor supply dan demand dalam teori penentuan harga, seperti disebutkan oleh seorang
ekonom sekuler, James Tobin (1980) bahwa: "God gave us two eyes so that we could
watch both supply and demand" (Tuhan telah menganugerahkan manusia dua mata
sehingga kita dapat melihat kedua faktor penawaran dan permintaan).
Imam al-Ghazali (1058-1111 M)
Di dalam bukunya Ihya Ulum al-Din, Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa penentuan
harga terhadap barang dan jasa dalam masyarakat adalah merupakan suatu proses yang
alami (natural order). Dalam ulasannya, beliau memberi contoh bahwa para petani yang
bercocok tanam dengan keterbatasan alat-alat pertanian yang tersedia di satu pihak, dan
di pihak lain para tukang kayu dan tukang besi yang tidak memiliki beras untuk dimakan,
pada gilirannya, untuk memenuhi kebutuhan mereka, maka mereka akan saling tukar
menukar barang yang mereka produksikan. Petani menukar beras dengan alat-alat
pertanian yang mereka perlukan dari tukang besi dan tukang kayu. Proses tukar menukar
barang ini yang dalam istilah ekonomi disebut dengan ―Barter‖ ini baru akan berlaku bila
antara kedua mereka memiliki keinginan yang sama (similar wants). Bila keinginan
mereka berbeda, maka barter ini sangat mustahil untuk berlaku.
Kesulitan ini telah mendorong lahirnya sebuah pasar (trading places) dimana semua
mereka yang ingin ber-barter dengan mudah akan dapat menemukan partner bisnis yang
~ 45 ~
mempunyai keinginan yang sama. Karena dengan adanya pasar ini, maka para pembeli
dan penjual akan datang dari satu tempat ke tempat yang lain mencari dan untuk
memenuhi kebutuhan mereka. Perjalanan mencari pasar ini akan mendorong penciptaan
alat-alat transportasi untuk mempermudah perjalanan bisnis. Oleh karena itu, akumulasi
untung yang dilakukan oleh para pedagang (traders) adalah suatu motif yang wajar
karena dalam aktivitas bisnis ini selalu tidak terlepas dari faktor ketidakpastian
(uncertainty) dan berbagai resiko (risks). Namun, menurut al-Ghazali, keuntungan yang
ingin diperolehi oleh pedagang hendaklah bukan keuntungan yang berlebihan (excessive
profit). Karena, menurut beliau, keuntungan yang hakiki dalam bisnis bukannya
keuntungan material yang diperoleh dari pasar di dunia fana ini, tetapi melainkan
keuntungan yang diperoleh di pasar akhirat kelak (ultimate market) dengan menjalankan
bisnis sesuai dengan cara-cara yang diridhai Allah swt.
Dalam konteks ini, penentuan harga terhadap suatu barang dan jasa, menurut Imam al-
Ghazali adalah sangat bergantung kepada para pembeli (demand-side). Jika para petani
dengan mudah menemui para pembeli, maka mereka dapat menjualnya dengan harga
mahal, dan sebaliknya bila mereka sukar mencari pembeli yang ingin membeli beras
mereka, maka mereka akan menjualnya dengan harga yang murah. Walaupun beliau
tidak mendiskusikan supply atau demand dalam konteks ekonomi modern, namun
skenario ini dalam ilmu ekonomi konvensional telah digambarkan dengan bentuk kurva
penawaran (supply curve) yang berslope positif (upward sloping supply curve). Dalam
kitabnya, al-Ghazali juga sempat menyinggung konsep elastisitas harga permintaan
dengan menyebutkan bahwa: ―pemotongan terhadap margin keuntungan dengan
melakukan penurunan harga akan menyebabkan kenaikan penjualan dan juga
keuntungan‖. Di akhir penjelasan tentang teori harga dalam kitabnya, al-Ghazali memberi
solusi untuk menurunkan harga terhadap barang yang mahal dengan cara membatasi
jumlah permintaan (quantity of demand).
~ 46 ~
Ibn Taymiyah (1263-1328)
Kaitannya dengan mekanisme pasar dan bagaimana harga sesuatu barang itu ditentukan,
di dalam kedua kitabnya yang terkenal, al-Hisbah dan al-Siyasah al-Syari'ah, Ibn
Taymiyah dengan sangat jelas menyebutkan bahwa: "kenaikan dan penurunan harga
tidak selamanya disebabkan oleh ketidakadilan yang dilakukan oleh orang lain.
Kadangkala, ketidakstabilan harga ini disebabkan oleh kekurangan produksi atau
penurunan jumlah barang import yang diperlukan. Jadi, jika keinginan untuk membeli
barang itu meningkat sementara ketersediaan barang tersebut terbatas, maka harga akan
naik. Sebaliknya, jika ketersediaan barang itu melimpah ruah sementara keinginan
konsumen untuk membeli barang tersebut menurun, maka harga akan turun. Sedikit atau
banyaknya ketersediaan barang mungkin tidak disebabkan oleh tindakan seseorang, dan
hal ini juga tidak semestinya disebabkan oleh praktek-praktek yang tidak adil dalam
bisnis".
Pendapat beliau di atas merefleksikan bahwa ketidakstabilan harga mungkin disebabkan
oleh praktek ekonomi yang berlaku pada masa tersebut dimana banyak terjadi praktek
ketidakadilan dalam ekonomi, seperti praktek manipulasi, dan tindakan yang melanggar
hukum (transgression) serta berbagai malpraktek lain. Walaupun demikian, beliau tidak
menafikan bahwa kenaikan dan penurunan harga barang itu mungkin disebabkan oleh
tekanan pasar (market pressure) yang berlaku secara alami. Selanjutnya, dari pendapat
beliau di atas, kita dapati bahwa sumber utama penawaran barang dan jasa adalah berasal
dari produksi dalam negeri dan import dari luar negeri.
Dalam membahas teori penentuan harga, analisa beliau tidak pernah terlepas dari takdir
Tuhan. Dalam situasi normal, bila seseorang menjual barangnya menurut kebiasaan yang
berlaku dengan tidak melibatkan tindakan manipulasi dan terjadinya kenaikan harga yang
disebabkan oleh berkurangnya jumlah barang yang tersedia atau disebabkan oleh
kenaikan jumlah produksi, maka menurut beliau ini adalah semata-mata terjadi
disebabkan oleh takdir Tuhan.
~ 47 ~
Di samping itu, beliau juga mengidentifikasikan beberapa faktor lain yang menentukan
jumlah permintaan dan penawaran, yang pada gilirannya, akan mempengarungi harga
pasar. Hal ini sangat jelas diilustrasikan dalam statemen beliau sebagai berikut:
"Keinginan seseorang untuk memiliki barang adalah berbeda antara satu sama lain.
Pertimbangan ini disebabkan oleh jumlah ketersediaan barang dan jasa yang diminta di
pasar. Barang dan jasa yang langka biasa akan diminati banyak orang ketimbang ketika
barang dan jasa itu melimpah ruah berada di pasar. Perbedaan ini juga disebabkan oleh
jumlah konsumen yang ingin membelinya. Jika jumlah konsumen yang meminta barang
dan jasa itu banyak, maka harganya akan naik dibandingkan dengan ketika jumlah
konsumen yang ingin membeli barang dan jasa tersebut sedikit. Tinggi rendahnya harga
sesuatu barang dan jasa juga dipengaruhi oleh kekuatan atau kelemahan kebutuhan akan
barang dan jasa tersebut. Jika kebutuhan akan barang dan jasa tersebut urgen, maka harga
barang dan jasa tersebut akan naik ketimbang ketika kebutuhan akan barang dan jasa
tersebut melemah. Kemudian, harga barang dan jasa juga bervariasi tergantung dengan
siapa dan bagaimana barang dan jasa itu diperjualbelikan. Jika jual beli itu dilakukan
dengan orang yang bisa dipercaya dalam pembayaran hutang (jika dijual secara kredit)
dan dapat membayar hutangnya sekaligus, maka harga murah adalah memadai ketimbang
menjual kepada pembeli yang diragukan kejujurannya dan tidak memiliki keupayaan
untuk membayar hutangnya sekaligus dan tepat waktu".
Dari pendapat beliau di atas dapat dipelajari bahwa demand dan supply itu ditentukan
oleh faktor-faktor, di antaranya, intensitas dan besarnya jumlah permintaan, kelangkaan
dan kelebihan barang di pasar, ketersediaan penjualan secara kredit, dan adanya diskon
untuk pembayaran secara kas. Ini juga menunjukkan bahwa penjualan secara kredit dan
pemberian diskon bagi pembeli yang sanggup membayar secara kas adalah sesuatu yang
lumrah berlaku pada masa itu. Bila kita bandingkan dengan pendapat Abu Yusuf dan al-
Ghazali di atas, maka Ibn Taymiyah tidak hanya melihat demand dan supply sebagai
faktor penentu harga. Namun, lebih jauh lagi, beliau melihat insentif, disinsentif,
ketidakpastian, dan resiko dalam bisnis juga memainkan peran penting dalam
menentukan harga barang dan jasa di pasar.
~ 48 ~
Lebih lanjut, dalam mengatasi ketidakadilan dalam berbisnis, beliau sangat menentang
semua usaha yang bersifat memaksa penjual untuk menjual barang dan jasa yang mereka
tidak ingin menjualnya. Begitu juga sebaliknya, usaha-usaha untuk menghalang para
penjual daripada menjual barang dan jasa yang tidak dilarang Islam adalah suatu tindakan
yang tidak berkeadilan. Ini menunjukkan bahwa semua orang memiliki hak yang sama
untuk memasuki dan keluar dari pasar (freedom to enter or exit a market). Hal ini
memperlihatkan bahwa beliau sangat menentang peraturan yang berlebihan (excessive
regulation) dalam mendikte tingkat harga ketika pasar berada dalam keadaan stabil.
Namun demikian, dalam menghadapi pasar yang tidak normal dimana harga barang dan
jasa terlalu tinggi dan berada jauh dari jangkauan konsumen, maka hendaklah para
produsen menjual barang produksi mereka pada harga terjangkau sesuai dengan harga
barang-barang sejenis (the price of the equivalent) yang beredar di pasar. Inilah yang
disebut oleh Ibn Taymiyah dengan konsep harga yang adil (just price). Untuk menjamin
semua barang dan jasa itu dijual pada harga yang adil, misalnya, sebagai akibat dari
praktek monopoli, maka peran aktif pihak penguasa adalah sangat diperlukan. Dalam hal
ini, kebijakan pengontrolan harga (price control policy) untuk menjamin terwujudnya
harga yang adil adalah hal yang mutlak harus dipikul pemerintah.
Dari pembahasan di atas, semakin jelas bahwa konsep mekanisme pasar dan teori harga
yang diketengahkan oleh Ibn Taymiyah tidak terlepas dari prinsip-prinsip keadilan
(justice), kebebasan dalam memilih (freedom of choice), dan kejujuran (fairplay)
Ibn Khaldun (1332-1404)
Di dalam kitabnya yang terkenal, al-Muqaddimah, Ibn Khaldun telah membagikan
barang dan jasa ke dalam dua jenis, yaitu barang kebutuhan pokok (necessary goods) dan
barang mewah (luxury goods). Kaitannya dengan penentuan tingkat harga, beliau
mengatakan bahwa ketika sebuah negara yang sedang berkembang yang ditandai dengan
bertambahnya jumlah penduduk, maka harga barang kebutuhan pokok akan turun
dibandingkan dengan harga barang mewah yang cenderung menjadi lebih mahal. Alasan
beliau adalah ketika jumlah permintaan barang kebutuhan pokok meningkat, maka para
~ 49 ~
produsen akan lebih mengkonsentrasikan untuk memproduksi lebih banyak barang-
barang kebutuhan pokok ketimbang barang mewah yang jumlah permitaannya relatif
konstan. Akibat banyaknya jumlah barang kebutuhan pokok yang diproduksikan, maka
kenaikan harga barang tersebut dengan sendirinya akan terkawal.
Sedangkan produksi barang mewah tidak begitu menarik perhatian pihak produsen,
sehingga harga barang mewah dengan sendirinya akan naik akibat terbatasnya
ketersediaan barang tersebut di pasar. Pendapat beliau ini sangat sesuai dengan hukum
permintaan (the law of demand) dan hukum penawaran (the law of supply) yang dapat
kita pelajari dalam ilmu ekonomi barat sekarang, yang masing-masing mengatakan
bahwa "jika jumlah permintaan terhadap sesuatu barang dan jasa adalah banyak, maka
harga barang dan jasa tersebut akan mahal, dan sebaliknya jika jumlah permintaan
sedikit, maka harga barang dan jasa tersebut akan murah", dan "jika jumlah barang dan
jasa yang ditawarkan adalah banyak, maka harganya akan turun, dan sebaliknya jika
jumlah barang dan jasa yang ditawarkan sedikit, maka harga barang akan naik".
Di samping itu, beliau juga mendeskripsikan pengaruh kenaikan dan penurunan
penawaran terhadap harga sesuatu barang. Beliau mengatakan bahwa "ketika barang yang
dibawa dari luar (di import) adalah sedikit, maka harga barang tersebut akan naik.
Sebaliknya, tatkala barang yang dibawa dari luar yang jaraknya berdekatan dan kondisi
transportasinya aman, sehingga dengan mudah untuk membawa barang masuk dari luar
dalam jumlah yang tidak terbatas, maka harga barang tersebut akan menurun".
Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa seperti halnya Ibn Taymiyah, Ibn Khaldun
juga mengakui peran kedua faktor permintaan dan penawaran dalam menentukan harga
barang dan jasa di pasar. Oleb sebab itu, dalam pembahasannya tentang mekanisme pasar
dan teori harga, Ibn Khaldun lebih menekankan pembahasannya sesuai dengan realitas
dan fakta-fakta di lapangan, sedangkan Ibn Taymiyah lebih cendrung untuk
mendiskusikan pembahasannya tentang isu-isu kebijakan (policy issues) pasar.
~ 50 ~
Kesimpulan
Dari pembahasan di atas, dapat kita tarik konklusi bahwa ide-ide tentang mekanisme
pasar dan teori harga telah ada jauh sebelum pertengahan abad ke-18 M. Bahkan konsep
mekanisme pasar dan teori penentuan harga barang dan jasa yang dikemukan oleh
pemikir dan tokoh ulama Islam tersebut di atas cukup jelas menceritakan kinerja pasar
dan faktor-faktor yang menentukan harga barang dan jasa. Bukti ini dengan jelas telah
menolak mentah-mentah pendapat para pemikir ekonomi konvensional, seperti
Schumpeter yang mengatakan bahwa tidak ditemukannya konsep mekanisme pasar dan
teori harga sebelum abad ke-18 M. Disadari atau tidak, padahal hampir dari semua teori
ekonomi yang dibanggakan para pemikir ekonomi barat sekarang adalah bersumber dari
teori-teori dasar yang dikemukan oleh para pemikir Islam.
~ 51 ~
BAB 6
FUNGSI UANG DALAM EKONOMI ISLAM
Walaupun pada awal kemunculan pemikiran ekonomi Keynesian, eksistensi uang dalam
ekonomi belum diakui sepenuhnya. Namun seiring dengan peredaran masa dan sejalan
dengan perubahan ekonomi, fungsi dan peran uang dalam ekonomi semakin penting
sehingga ia tidak bisa dipisahkan dari sistem ekonomi. Hal ini menyebabkan para
ekonom berkonklusi bahwa uang merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan
tingkat aktivitas ekonomi sebuah negara. Setidaknya ada dua alasan mendasar kenapa
para ekonom melihat uang itu penting dalam aktivitas perekonomian. Pertama adalah
karena uang dapat digunakan untuk menentukan jumlah nominal, seperti tingkat harga,
dan kedua karena ia juga dapat dijadikan standard untuk menentukan jumlah riel, seperti
jumlah out put riel dan tenaga kerja riel.
Dalam sejarah Islam, kesadaran akan pentingya uang dalam sebuah sistem ekonomi telah
muncul jauh sebelum ilmu ekonomi itu diakui sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri.
Peran uang dalam ekonomi Islam telah didiskusikan oleh Iman al-Ghazali (1058-1111 M)
dalam kitabnya yang terkenal, ―Ihya Ulum al-Din”. Menurut beliau, manusia
memerlukan uang sebagai alat perantara/pertukaran (medium of exchange) untuk
membeli barang dan jasa. Sementara itu, Ibn Taymiyah (1263) menyebutkan bahwa uang
itu tidak hanya berfungsi sebagai medium of exchange, tetapi ia juga berfungsi sebagai
alat untuk menentukan nilai (measurement of value). Akhirnya, dalam membahas peran
uang dalam ekonomi, Ibn Qayyim sependapat dengan al-Ghazali, sementara itu Ibn
Khaldun (1332-1404) lebih cenderung bersetuju dengan pendapat Ibn Taymiyah.
Karena ada instrumen-instrumen ekonomi konvensional baik yang bersifat instrumen
policy atau institusional yang tidak sejalan dengan ajaran al-Qur‘an dan Hadits, maka
fungsi dan peran uang di dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam adalah
berbeda. Sebab mendasar mengapa fungsi uang dalam ekonomi Islam dan ekonomi
konvensional berbeda adalah karena dalam sistim ekonomi Islam, interest (riba),
perjudian (gambling) dan unsur-unsur tidak jelas, gharar (uncertainty) itu diharamkan
~ 52 ~
agama. Sedangkan ekonomi konvensional melihat semua unsur ini sebagai sesuatu yang
normal dan legal.
Dalam ekonomi konvensional, J. M. Keynes (1936) di dalam buku terkenalnya, ―General
Theory of Employment, Interest and Money” mengemukan sebuah teori tentang
permintaan uang yang dikenal dengan liquidity preference (preferensi likuiditas). Teori
preferensi likuiditas ini menyebutkan bahwa ada tiga motif utama yang menentukan
jumlah permintaan uang dalam sebuah perekonomian, yaitu: (i) motif transaksi
(transaction motive); (ii) motif berjaga-jaga (precautionary motive); dan (iii) motif
spekulasi (speculative motive).
Motif transaksi didefinisikan sebagai suatu motif permintaan uang yang diperlukan untuk
kebutuhan sebuah transaksi. Karena transaksi ini biasanya dilakukan oleh individu dan
pebisnis, maka J. M. Keynes membagi motif transaksi ini ke dalam: (a) motif pendapatan
(income motive), dan; (b) motif bisnis (business motive). Sementara itu, motif berjaga-
jaga adalah suatu motif untuk memegang uang dengan tujuan mengantisipasi produksi-
produksi yang tidak dapat diprediksikan di masa-masa mendatang. Dalam ekonomi
konvensional, motif ini dipengarahui oleh tingkat pendapatan individu dan tingkat suku
bunga. Sedangkan, permintaan uang dengan motif spekulasi itu dimaksudkan untuk
menghindari kemerosotan nilai modal (capital value) akibat penurunan aktivitas
ekonomi. Untuk menghindari kerugian ini, biasanya para pelaku bisnis menginvestasikan
uangnya (modal) di pasar-pasar saham yang keuntungannya itu sangat ditentukan oleh
perbedaan tingkat suku bunga.
Jadi dapat dikatakan bahwa dua motif pertama permintaan akan uang, yaitu motif
transaksi dan motif berjaga-jaga adalah berkaitan langsung dengan fungsi uang sebagai
alat pertukaran (tool of exchange) dalam sebuah kegiatan perekonomian. Sedangkan
motif spekulasi lebih erat kaitannya dengan fungsi uang sebagai alat penyimpan harga
atau kekayaan (store of value or wealth). Bila kita komparasikan antara pendapat para
pemikir ekonomi Islam dengan pendapat Keynes di atas, jelas terlihat bahwa kecuali
~ 53 ~
motif memegang uang untuk berspekulasi, semua motif untuk memiliki uang lainnya
adalah disetujui oleh pemikir-pemikir ekonomi Islam seperti disebutkan di atas.
Kita ketahui bahwa motif spekulasi ini dimaksudkan untuk meraup keuntungan dan
menumpuk kekayaan dengan memanfaatkan perubahan tingkat suku bunga dari masa ke
masa. Melihat karakteristik dan cara spekulasi itu dipraktekkan dalam dunia bisnis yang
melibatkan bunga (interest) dengan menghalalkan segala cara, mengedepankan nilai
ketamakan (greediness) tanpa mempedulikan nilai-nilai keadilan, maka Islam secara
tegas menentang motif spekulasi. Salah satu contoh dari motif ini adalah tindakan
monopoli (ihtikar). Dalam memonopoli barang dan jasa sebagai salah satu tindakan
spekulasi, Imam al-Ghazali membedakan antara monopoli pada saat kekurangan
(shortages) atau ekonomi dalam paceklik dan pada saat kelebihan (surplus) barang dan
jasa. Dalam keadaan shortages, praktek monopoli adalah sangat bertentangan dengan
nilai-nilai ekonomi Islam. Sementara itu, pemikir ekonomi Islam tidak melihat tindakan
monopoli pada saat barang dan jasa dalam keadaan surplus sebagai sesuatu tindakan yang
bertentangan dengan nilai-nilai moralitas dan norma-norma keislaman. Hal ini
dikarenakan pada saat kelebihan barang dan jasa beredar di pasar, tindakan monopoli
tidak akan mempengaruhi harga barang dan jasa sehingga tidak akan membahayakan
kesejahteraan umat. Jadi jelaslah bagi kita bahwa, motif spekulasi ini sangat bertentangan
dengan nilai-nilai keadilan karena selain melibatkan riba (interest), ia juga melibatkan
unsur-unsur perjudian (gambling) dan juga melibatkan unsur-unsur ketidakpastian
(gharar).
Seperti disebutkan sebelumnya, kedua motif transaksi dan motif berjaga-jaga tidaklah
dilihat sebagai motif permintaan uang yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-
norma keislaman. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa dalam melakukan transaksi,
seseorang itu bisa berbuat sekehendak hatinya dengan melanggar ketentuan Allah swt,
seperti melakukan manipulasi, eksploitasi, transaksi barang-barang illegal, transaksi yang
melibatkan bunga, dan monopoli. Motif transaksi ini hendaklah dilakukan berdasarkan
konsep transaksi Islami. Sedangkan, motif berjaga-jaga adalah suatu motif permintaan
uang yang sangat dianjurkan Islam, asal saja motif itu tidak semata-mata termotivasi
~ 54 ~
untuk meraup keuntungan semaksimal mungkin, dengan memanfaatkan perbedaan suku
bunga ketika menyimpan dan mengeluarkan uang dari tempat penyimpanan uang (bank).
Karena motif ini merupakan motif seseorang untuk menabung demi kepentingan masa
depan, terutama dalam menghadapi kesulitan-kesulitan ekonomi yang tidak dapat
diperkirakan, maka motif ini sangat sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan
pertimbangan untuk membantu orang lain (altruistic consideration). Jadi motif ini sangat
berguna tidak hanya untuk meringankan beban diri sendiri, tetapi juga untuk membantu
meringankan beban orang lain tatkala menghadapi musibah ekonomi. Namun, tentu saja
bantuan yang diulurkan untuk meringankan beban orang lain itu hendaklah tidak dalam
bentuk pinjaman berbunga, tetapi sebaiknya dalam bentuk bantuan bebas bunga, Qardh
al-Hasan.
Di samping itu, perlu diketahui bahwa Islam melarang memperlakukan uang sama
dengan barang (commodity) yang bisa diperjualbelikan. ―In Islam, money is not identical
with commodity that can be traded for the purpose of making profit” (Dalam Islam, uang
tidaklah identik dengan barang yang dapat diperjualbelikan dengan tujuan untuk meraup
keuntungan). Islam hanya melihat uang itu sebagai alat tukar, alat perantara, dan alat
untuk menentukan nilai, bukan sebagai barang yang diperjualbelikan. Ini bermakna
bahwa Islam tidak membenarkan uang itu diperjualbelikan di pasar valuta asing (valas)
dengan tujuan spekulasi dan memperkaya diri. Keuntungan memperjualbelikan uang di
pasar valuta asing yang bersumber dari perbedaan harga beli dan harga jual dan
perbedaan tingkat bunga antara satu negara dengan negara lain dimana valuta asing
diperjualbelikan adalah bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Sebagai contoh, kita
membeli Dollar Amerika dengan menggunakan Rupiah, dan kemudian menjual Dollar
Amerika untuk membeli Poundsterling Inggris, dan kemudian Poundsterling dijual untuk
membeli Deutchmark Jerman, dan akhirnya Deutchmark dijual untuk kembali membeli
Rupiah, dan seterusnya. Dari proses jual beli ini, yang sering disebut dengan Arbitraging,
biasanya keuntungan ataupun kerugian yang di dapat adalah tidak setimpal dengan
pengorbanan yang dilakukan dan waktu yang diperlukan. Bisa jadi dalam masa yang
sesingkat-singkatnya, seperti kasus George Soros, yang dituding sebagai penyebab utama
terjadinya malapetaka krisis moneter di sebagian besar negara Asia Timur pada
~ 55 ~
pertengahan tahun 1997, keuntungan yang di dapat dengan memperjualbelikan uang di
pasar valuta asing dalam jumlah berbilion-bilion. Akibat tindakan Soros ini, tidak sedikit
negara yang langsung ambruk fundamental ekonominya, terutama Indonesia. Karenanya,
tidak sedikit rakyat negeri kepulauan ini harus menderita karena krisis ekonomi yang
menerpa sampai beberapa tahun kemudian. Inilah yang menjadi alasan mengapa Islam
tidak membenarkan uang itu diperlakukan sama seperti barang yang bebas
diperjualbelikan, seperti dipraktekkan dalam ekonomi barat.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengharaman interest
(riba) dalam ekonomi Islam menyebabkan tidak semua fungsi uang dalam ekonomi
konvensional bisa diimplementasikan dalam sistem ekonomi Islam. Keterlibatan interest,
gambling dan gharar dalam motif permintaan uang untuk berspekulasi telah
menyebabkan motif ini secara keras ditentang oleh Islam. Sementara dua motif lainnya,
motif permintaan uang untuk bertransaksi dan untuk berjaga-jaga tidak dipandang
sebagai motif memegang uang yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam sejauh elemen-
elemen riba tidak memotivasi mereka dalam kedua motif permintaan uang tersebut. Tidak
seperti halnya prinsip ekonomi konvensional, prinsip ekonomi Islam menentang keras
uang itu untuk diperlakukan sama dengan barang-barang (commodities) yang dapat
diperjualbelikan semata-mata untuk meraih keuntungan.
~ 56 ~
BAB 7
KONSEP MENABUNG DALAM EKONOMI ISLAM
Sebagai agama yang syumul, Islam mengatur umatnya dalam berbagai aspek kehidupan,
tidak hanya dalam dalam bidang sosial, politik dan ritual semata, tetapi juga dalam
bidang ekonomi. Ini berimplikasi bahwa Allah swt telah menyediakan panduan atau
aturan main (the rule of games) dalam setiap aspek kehidupan, termasuk di bidang
ekonomi. Panduan ini telah diatur sedemikian rupa oleh Allah swt dalam berbagai
sumber hukum Islam baik secara langsung maupun tidak langsung yang eksistensinya
sangat berbeda dengan hukum ekonomi buatan manusia. Hal inilah, di antaranya, telah
menempatkan sistim ekonomi Islam jauh lebih unggul dibandingkan dengan sistim
ekonomi kapitalis dan komunis. Keunggulan sistem ekonomi Islam ini, misalnya, dapat
dilihat bagaimana signifikansi konsep menabung dalam Islam dalam rangka untuk
menuju sebuah negara yang damai dan makmur (thayyibat al-rabb-al-ghafur).
Islam adalah agama yang bernuansakan pertengahan (moderate) dimana umat Islam
senantiasa diarahkan untuk hidup hemat dan berkonsumsi secara tidak mubazir
(extravagance). Penghematan ini harus dilakukan dengan mengurangi kecenderungan
untuk mengkonsumsi (propensity to consume) barang dan jasa. Jumlah pendapatan yang
tersisa dari konsumsi, pada gilirannya, akan memungkinkan seorang Muslim untuk
cenderung menabung (propensity to save) lebih banyak. Larangan untuk berbelanja
secara berlebihan (extravagance) dan tuntunan agama untuk mengkonsumsikan barang
dan jasa berdasarkan konsep halal dan haram, telah mendorong umat Islam agar gemar
menabung. Secara implisit ini berindikasi bahwa seorang Muslim yang baik yang
senantiasa mematuhi panduan Syari‘ah akan cenderung menabung lebih banyak
dibandingkan dengan orang non-Muslim (ignorant people). Namun yang jadi
permasalahan sekarang adalah mengapa banyak negara Muslim jauh lebih terbelakang
(backward) baik dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi dibandingkan dengan
negara sekuler? Padahal kita ketahui bahwa tingkat tabungan (saving) merupakan salah
satu indikator penting terhadap kemajuan setiap negara. Apakah karena ketaqwaan kita
~ 57 ~
masih diragukan, sehingga kita belum secara komprehensif dan perfek mengikuti aturan
Ilahi?
Tulisan ini tidak difokuskan untuk menjawab persoalan-persoalan di atas. Tulisan ini
hanya coba menganalisa konsep menabung dalam ekonomi Islam dengan menyuguhkan
beberapa dalil naqli terhadap kevaliditasan menabung dalam Islam, memberikan alasan-
alasan potensialitas menabung dalam Islam, memaparkan model tabungan yang Islami
dan mengilustrasikan besarnya ganjaran pahala menabung dalam Islam.
Validitas Menabung dalam Islam
Tidak sedikit ayat al-Qur‘an dan Hadits, baik yang secara langsung maupun tidak
langsung, yang mendorong umat Islam untuk menabung. Konsep kesederhanaan
(moderation) dalam berbelanja sangat tegas disebutkan Allah swt dimana Islam sangat
membenci praktek menghambur-hamburkan uang (mubazir) dalam mengkonsumsi
barang dan jasa. Kebencian Allah swt terhadap praktek mubazir ini adalah cukup
beralasan karena pemubaziran akan menyebabkan kehidupan masa depan seseorang
menjadi tidak pasti. Hidup tanpa perencanaan ekonomi yang matang, tentunya akan
menggangu aktivitas sehari-hari kita baik dalam bergaul dengan sesama manusia (Hablun
min al-Nas) maupun dalam bertaqarrub dan berubudiyah dengan sang Khaliqnya
(Hablun min al-Allah). Hal ini disebabkan karena tanpa memiliki jumlah tabungan yang
memadai, kita akan menghadapi kesulitan ekonomi yang tidak dapat diprediksikan di
masa-masa mendatang. Agar memiliki jumlah tabungan yang memadai untuk
menghadapi semua dugaan ekonomi, maka al-Qur‘an memberi solusi agar umatnya tidak
berbelanja secara berlebih-lebihan dan juga tidak terlalu kikir, seperti disebutkan dalam
beberapa ayat-ayat berikut: ―Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada
lehermu dan janganlah kamu terlalu menghulurkan karena itu kamu menjadi tercela dan
menyesali‖ (Q.S. al-Isra‘: 29); ―Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-
saudara syaitan...‖ (Q.S. al-Isra‘: 27); “...makan dan minumlah kamu, dan janganlah
berlebih-lebihan...” (Q.S. al-A‘raf: 31); dan ―Dan orang-orang yang apabila
membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak (pula) kikir...” (Q.S. al-
Furqan: 67).
~ 58 ~
Sementara itu, Rasulullah saw dalam banyak Haditsnya memberi peringatan kepada
umatnya agar gemar menabung sebagai cara jitu menghadapi kesulitan ekonomi yang
terjadi diluar dugaan dan sekaligus untuk membasmi kemiskinan. Dapat disimak dari
beberapa Hadist berikut: “...Rasulullah saw pernah membeli kurma dari Bani Nadhir dan
menyimpannya untuk perbekalan setahun buat keluarga...‖ (H.R. Bukhari); ―Simpanlah
sebagian dari harta-harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih
baik bagimu‖ (H.R. Bukhari); dan “...saya (Rasulullah) sungguh berlindung dari
kemiskinan, kelangkaan dan kejahatan....” (H. R. Bukhari).
Berdasarkan maksud beberapa ayat al-Qur‘an dan Hadits di atas, kita dapat melihat
bahwa kegiatan menabung adalah sesuatu yang sangat digalakkan dalam Islam. Namun
ini tidak berarti bahwa Islam membenarkan umatnya untuk berlaku kikir dengan
menumpuk harta sesuka hatinya dan kemudian membiarkan harta itu tidak produktif.
Tumpukan harta yang tidak diinvestasikan dalam sektor-sektor produksi justeru akan
memperparah kondisi ekonomi karena langkanya kesempatan kerja sebagai konsekuensi
dari kurangnya jumlah permintaan terhadap barang dan jasa yang dijual di pasar.
Terbatasnya modal yang diinvestasikan dalam sektor produksi akan menyebabkan proses
produksi terkendala sehingga jangankan untuk merekrut tenaga kerja baru, kadang kala,
untuk membayar gaji pekerja yang sudah ada agak susah. Keadaan ini sering berakhir
pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan atau buruh-buruh karena
ketidakmampuan majikan untuk membayar gaji akibat rendah atau tidak lakunya barang
dan jasa yang mereka produksikan, mungkin akibat melemahnya animo atau kemampuan
daya beli (purchasing power) masyarakat. Ketiadaan sumber pendapatan yang tetap
menyebabkan para penganggur (mereka yang dipecat atau belum mendapat pekerjaan)
tidak berdaya untuk membeli barang dan jasa yang ditawarkan di pasar. Terbatasnya
jumlah pembeli barang dan jasa, pada akhirnya, akan mempengaruhi proses produksi
sehingga memungkinkan terjadi pemecatan (retrenchment) karyawan yang berkelanjutan
karena ketidaksanggupan para majikan membayar gaji akibat semakin berkurangnya
keuntungan yang diperoleh pihak produser.
~ 59 ~
Kenapa dalam Ekonomi Islam Menabung itu Potensial?
Seperti disebutkan di atas, selain galakan agama untuk berkonsumsi secara sederhana
(moderation), larangan bertindak mubazir, dan terbatasnya jumlah barang dan jasa yang
bisa dikonsumsikan sesuai dengan konsep halal dan haram dalam Islam, telah
menyebabkan jumlah tabungan para Muslim jauh lebih potensial dari non-Muslim. Tidak
seperti dalam ekonomi konvensional, Islam melarang umatnya untuk mengkonsumsi
barang dan jasa yang haram hukumnya karena ia akan dapat memudharatkan baik
kesehatan sistem ekonomi maupun kesehatan tubuh mereka. Contoh, Islam tidak
membenarkan umatnya mangadopsi hukum riba, mengkonsumsi makanan haram, seperti
babi, alkohol, dan sebagainya. Karena jumlah barang dan jasa yang bisa dikonsumsikan
terbatasnya, maka kecenderungan umat Islam untuk menabung akan semakin tinggi.
Faktor inilah yang menyebabkan menabung semakin potensial dalam Islam.
Tujuan kita berpedoman pada konsep halal dan haram dalam mengkonsumsi barang dan
jasa, menurut Akram Khan (1983) adalah sebagai pengontrol atau patron dalam
membelanjakan harta untuk tujuan konsumsi sehingga menyisakan jumlah harta
maksimal yang bisa ditabung. Sementara itu A. M. Sadeq (1992), seorang mantan
professor bidang ekonomi pembangunan Islam di International Islamic University
Malaysia (IIUM), lebih jauh melihat bahwa faktor-faktor penyebab potensialnya
tabungan dalam Islam tidak hanya seperti disebutkan di atas. Beliau melihat bahwa
kewajiban umat Islam untuk menggunakan sumber daya alam dan sumber daya manusia
(natural and human resources) secara optimal dan keharusan untuk memobilisasi
tabungan secara produktif dimana tabungan itu harus disalurkan untuk diinvestasikan di
sektor-sektor yang menghasilkan keuntungan, juga merupakan di antara faktor-faktor
penting lainnya yang mendorong umat Islam untuk menabung. Di samping itu, Islam
melihat bekerja untuk memenuhi nafkah baik untuk dirinya maupun untuk orang yang
berada di bawah tanggungannya adalah merupakan bagian dari pada ibadat kepada Allah
swt. Ganjaran pahala yang diperolehi karena melakukan ibadat (bekerja keras dan
menabung) akan memotivasi umat Islam untuk bekerja lebih keras sehingga dari hasil
kerja keras tersebut mereka mendapat pendapatan/gaji yang lebih tinggi sehingga dengan
hidup hemat, maka jumlah sisa uang yang bisa mereka tabung/simpan akan lebih besar.
~ 60 ~
Walaupun demikian ada pendapat yang meragukan bahwa tingkat tabungan itu akan
terhambat karena penghapusan sistem bunga (interest/riba) dan keberadaan institusi zakat
dalam ekonomi Islam. Pendapat ini sebenarnya dilandaskan pada konsep tabungan
ekonomi klasik yang menyatakan bahwa tabungan itu bergantung secara positif pada
tingkat bunga. Semakin tinggi tingkat bunga, maka semakin tinggi animo masyarakat
untuk menabung karena mengharapkan keuntungan (bunga) yang lebih besar, begitu juga
sebaliknya. Ternyata hasil penelitian empiris telah membuktikan bahwa pandangan ini
adalah salah dan tidak cukup beralasan. Di dalam bukunya, ―Towards a Just Monetary
System‖, Umer Chapra (1985) membantah keras bahwa asumsi yang mengatakan
penghapusan bunga akan menghambat tingkat tabungan, yang pada gilirannya, akan
mengurangi formasi modal dalam ekonomi. Sedangkan pendistribusian zakat yang
ditujukan untuk mengimbangi jumlah pendapatan yang diterima antara masyarakat
miskin (have-not) dan kaya (have) justeru akan mempromosikan standar hidup
masyarakat miskin. Jika ini terealisasikan dimana masyarakat miskin dengan
pemberdayaan institusi zakat, secara ekonomi telah mampu mandiri bahkan telah well-
established, maka tidak perlu diragukan lagi bahwa kecenderungan untuk menabung
(propensity to save) masyarakat semakin meningkat karena telah berpartisipasinya
masyarakat miskin untuk menabung. Ini memperlihatkan bahwa sejak lebih dari 1.400
tahun yang lalu ekonomi Islam telah mengakui bahwa tabungan adalah sebagai salah satu
faktor dominan dalam pembangunan ekonomi.
Model Tabungan Islami
Penghapusan bunga (interest) merupakan perbedaan mendasar antara model tabungan
Islami dengan non-Islami. Oleh karena itu, fungsi tabungan dalam Islam sama sekali
tidak bergantung pada tingkat suku bunga seperti dalam ekonomi konvensional. Dalam
hal ini Umer Chapra (1985) hanya melihat bahwa pendapatan dan kebutuhan konsumsi
sekarang (current income and current consumption needs) dan pendapatan plus konsumsi
di masa mendatang (expected future income and consumption needs) adalah merupakan
faktor-faktor yang mempengaruhi tabungan seseorang. Sementara itu, Monzer Kahf
(1992) melihat bahwa banyak faktor lain yang mempengaruhi tingkah laku menabung
~ 61 ~
(saving behaviour) dalam Islam. Faktor-faktor itu adalah: (i) tingkat pendapatan; (ii)
keinginan mengumpulkan harta untuk menjadi kaya; (iii) ketersediaan barang dan jasa
untuk dikonsumsi; (iv) zakat; (v) tingkat keuntungan investasi; (vi) keinginan untuk
menyimpan harta dengan motif berjaga-jaga; dan (vii) kadar ketaqwaan kepada Allah.
Kecuali faktor konsumsi dan ketaqwaan, semua faktor di atas menurut Monzer Kahf
mempunyai hubungan positif dengan tingkat tabungan. Ini berimplikasi bahwa semakin
tingginya tingkat ketaqwaan seseorang maka akan semakin rendah tingkat tabungan
mereka. Karena pada umumnya mereka lebih memilih untuk menderma hartanya di jalan
Allah swt ketimbang untuk menyimpan apalagi untuk menumpuknya.
Secara realitas --- maksud saya bukan teoritis --- sebenarnya ketaqwaanlah yang
sepatutnya menyebabkan seseorang cenderung untuk menabung lebih banyak. Dalam hal
ini mungkin Monzer Kahf telah lupa bahwa derma atau sadaqah yang dikeluarkan oleh
orang-orang taqwa juga merupakan tabungan, yaitu tabungan untuk hari akhirat atau
tabungan ukhrawi. Namun tabungan ukhrawi (Hereafter saving) ini, menurut Akram
Khan (1983) adalah berbeda dengan tabungan duniawi (worldly saving) karena
keuntungan tabungan ukhrawi ini tidak hanya dapat dirasakan sekarang (di dunia)
manfaatnya tetapi juga imbalan mutlaknya akan didapat pada hari pembalasan (akhirat)
kelak. Kemusykilan lain bila derma atau sadaqah tidak dikategorikan ke dalam jenis
tabungan adalah hanya orang kikir dan orang bakhil-lah yang cenderung menabung lebih
banyak karena kekikiran dan ke-bakhil-an mereka, walaupun pada dasarnya pendapatan
mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan orang kaya raya yang
bertaqwa dan senantiasa mendermakan hartanya di jalan Allah swt. Derma dan sadaqah
orang taqwa untuk para dhu‘afa justeru akan meningkatkan kualitas hidup mereka
sebagai bagian dari proses pemberdayaan (empowerment) ekonomi sehingga tidak
mustahil bila pada akhirnya para dhu‘afa akan mampu untuk memiliki tabungan sendiri.
Bukankah skenario ini juga akan meningkatkan kecenderurangan umat Islam untuk
menabung!
~ 62 ~
Ganjaran Menabung yang Luar Biasa
Seperti disebutkan sebelumnya, galakan Islam agar umatnya senantiasa menabung adalah
tidak terlepas dari besarnya ganjaran pahala yang akan diperoleh dan janji untuk
memasuki syurga Allah bagi siapa saja yang menabung (bersedekah) di jalanNya. Ini
menunjukkan bahwa semakin tingginya tingkat ketaqwaan seseorang individu Muslim,
maka akan semakin tinggi jumlah keseluruhan tabungannya, yaitu tabungan duniawi plus
ukhrawi (Naziruddin Abdullah dan M. Shabri Abdul Majid, 2001). Kenyataan ini,
tentunya, akan mendorong umat Islam yang beriman dan bertaqwa menjadi penabung
yang sangat potensial. Karena imbalan pahala yang luar biasa bagi siapa yang menabung
di bank Allah, dengan memberi sedekah, menderma dan menafkahkan hartanya di jalan
Allah swt sebagai tabungan mereka untuk mencapai falah (kemenangan di dunia dan di
hari akhirat kelak), tidaklah dapat dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh
dengan menabung di bank-bank konvensional buatan manusia di negara manapun.
Hal ini seperti telah diabadikan Allah swt dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 261:
"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya
di jalan Allah) adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada
tiap-tiap bulir; seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia
kehendaki…". Makna ayat ini juga senada dengan sabda Rasulullah saw: ―Setiap amal
perbuatan kebajikan anak Adam akan dilipatkan pahalanya dengan sepuluh hingga tujuh
ratus kali ganda. Allah swt berfirman: „Melainkan puasa, karena sesungguhnya puasa
itu adalah untukKu dan Aku yang memberi balasannya…" (H.R. Muslim). Untuk
melihat lebih jauh tentang luar biasanya ganjaran menabung dalam Islam, lihat tulisan
Ramadhan dan Implikasinya dalam Ekonomi Islam di Bab VI buku ini.
Penutup
Dari uraian di atas, dapat kita catat bahwa Islam sangat menggalakkan umatnya untuk
menabung. Oleh karena jumlah tabungan merupakan indikator penting dalam sebuah
pembangunan ekonomi, maka dengan demikian dapatlah kita katakan bahwa Islam
adalah agama yang sangat pro dan cinta akan kemajuan (pro-development). Umat Islam
~ 63 ~
adalah umat penabung dan umat yang berwawasan pembangunan. Untuk itu, seseorang
yang beriman dan bertaqwa kepada Allah swt semestinya senantiasa berpedoman pada al-
Qur‘an dan al-Sunnah secara kaffah (comprehensive) dalam menjalankan segala aspek
kehidupannya. Artinya, ia tidak hanya berpandukan dalam aspek ritual semata tetapi juga
dalam aspek ekonomi. Mengingat perintah menabung merupakan bagian dari akhlaqul
karimah dan bagian dari kewajiban agama (religious duties), maka melaksanakannya
merupakan bagian ibadat kepada Allah swt yang sekaligus berganjarkan pahala.
~ 64 ~
BAB 8
ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL
Kewajiban zakat telah ditetapkan Allah swt melalui wahyu-Nya kepada kekasihNya,
Muhammad saw lebih dari 1.400 tahun yang lalu dengan tujuan utama untuk
memberdayakan ekonomi para dhu'afa di kalangan masyarakat Islam. Diharapkan dengan
adanya institusi zakat dalam Islam, baik tujuan pembersihan individu dan sosial maupun
tujuan pertumbuhan sosial-ekonomi untuk semua golongan masyarakat dengan mudah
dapat diwujudkan. Pentingnya peran zakat dalam sistem perekonomian Islam,
sebagaimana telah dinukilkan dalam beberapa ayat al-Qur‘an yang senantiasa meletakkan
perintah wajib zakat setelah kewajiban melaksanakan shalat lima waktu. Dari ke-lima
rukun Islam, zakat adalah merupakan satu-satunya kewajiban (instrumen) yang sangat
erat kaitannya dengan perekonomian umat. Hal ini karena zakat merupakan peraturan
Ilahiah (Divine Order), maka diyakini bahwa zakat akan jauh lebih berperan dalam
memberdayakan dan sekaligus mensejahterakan ekonomi umat dibandingkan dengan
peraturan-peraturan buatan manusia (man-made regulations) lainnya.
Walaupun demikian, kenyataannya adalah sangat sukar bagi kita untuk menemui negara-
negara yang didiami mayoritas umat Islam yang kondisi ekonominya jauh lebih maju
dibandingkan dengan negara-negara sekuler. Bahkan hampir semua negara Muslim
adalah tergolong sebagai negara terbelakang (under-developed countries) atau negara
sedang berkembang (developing countries). Mengapa hal ini terjadi? Apakah karena
belum adanya kesadaran umat tentang kewajiban membayar zakat dan pentingnya peran
zakat terhadap program pengentasan kemiskinan? Atau apakah karena institusi zakat
yang belum dapat difungsikan secara optimal? Mungkinkah karena para pengurus (amil)
zakat yang tidak bertanggung jawab sehingga menyebabkan hasil kumpulan zakat
tercecer kemana-mana? Tulisan bab ini bertujuan untuk melihat sejauhmana peran dan
pengaruh zakat sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal (fiscal policy) dalam dan
terhadap perekonomian umat. Dalam bahasan selanjutnya, kita akan menganalisa secara
sistematis fungsi zakat sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi
Islam, tujuan-tujuan kebijakan fiskal dan pengaruhnya terhadap ekonomi umat secara
~ 65 ~
komprehensif. Dalam pembahasan lebih lanjut, pengalaman beberapa negara Islam dalam
mengelola zakat coba kita presentasikan sebagai standar atau tolok ukur keberhasilan
pelaksanaan institusi zakat dalam sebuah negara.
Beberapa Asumsi
Sudah menjadi suatu persyaratan mutlak dalam ilmu ekonomi, untuk menganalisa sebuah
teori, ia tidak bisa terlepas dari asumsi-asumsi yang ditetapkan. Karena tanpa adanya
asumsi tertentu, ilmu ekonomi akan sangat sukar, kalau tidak mustahil, untuk
mengaplikasikan setiap teorinya dalam dunia nyata. Oleh karena itu, sebelum analisa
lanjutan terhadap peran dan pengaruh zakat terhadap perekonomian umat dibahas, maka
perlu terlebih dahulu kita menetapkan beberapa asumsi.
Agar zakat dapat berperan secara maksimal dalam memberdayakan ekonomi umat, maka
zakat haruslah dilaksanakan dalam sebuah negara Islam yang dijalankan berdasarkan a-
Qur‘an dan al-Hadist. Karena dalam sebuah negara Islam, semua praktek yang
bertentangan dengan syari‘at Islam, seperti riba, monopoli, perjudian, dan malpraktek
lainnya yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah diharamkan. Sebaliknya, semua
praktek yang digalakkan syari‘at Islam (good deeds) dilaksanakan dengan sepenuhnya
seperti, pelaksanaan hukum warisan, kesederhanaan dalam berkonsumsi, wujudnya hak-
hak kepemilikan individu dan sosial terhadap alat-alat produksi, dan berbagai amar
lainnya yang mendukung kesuksesan institusi zakat dalam mensejahterakan umat.
Namun, ini tidak bermakna bahwa zakat tidak akan dapat memberdayakan ekonomi
penduduknya di negara-negara Muslim, yang belum secara kaffah menganut sistem Islam
dalam semua aspek kehidupan.
Dalam kenyataannya, kecuali Sudan, Afghanistan dan Iran, memang tidaklah mudah
untuk menjumpai sebuah negara Islam yang benar-benar dijalankan berdasarkan hukum
Islam secara kaffah. Fakta ini menyebabkan banyak para ekonom Islam, seperti Faridi
(1980) misalnya, terpaksa melonggarkan asumsinya terhadap sebuah negara Islam dalam
~ 66 ~
menganalisa peran dan kedudukan zakat dalam perokonomian umat. Sejauhmana sebuah
negara telah dijalankan berdasarkan ajaran Islam dengan memiliki ciri-ciri penting
seperti; pengharaman riba, adanya institusi zakat; pelarangan monopoli; dan berbagai
malpraktek lainnya, maka zakat akan mempunyai pengaruh signifikan terhadap
pemberdayaan ekonomi umat. Asumsi ini sangat penting karena dengan adanya
pengharaman riba, sebagai contoh, maka akan menghambat pergerakan arus modal dan
tenaga kerja dari negara yang mengharamkan riba ke negara-negara yang membenarkan
riba dipraktekkan dalam aktivitas ekonomi mereka. Karena, pada umumnya, para
investor selalu mencari keuntungan maksimal dengan menanamkan modal mereka di
sektor-sektor atau negara-negara yang memberikan keuntungan dalam bentuk bunga
(riba) yang lebih tinggi. Tanpa pengharaman riba, pergerakan arus modal dan tenaga
kerja dari negara yang mengharamkan praktek riba ke negara yang membenarkan praktek
riba dilakukan dalam sistem ekonomi mereka akan terjadi dengan leluasa tanpa batasan.
Hal ini, secara otomatis, akan menyebabkan zakat tidak dapat berfungsi, berdampak dan
berperan optimal serta komprehensif terhadap pemberdayaan ekonomi umat.
Namun, jika semua asumsi di atas terpenuhi, maka kita optimis dan yakin bahwa zakat
sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam akan jauh lebih
efektif dan efisien dalam memberdayakan ekonomi umat dibandingkan dengan hanya
mengadopsi instrumen kebijakan fiskal ekonomi konvensional semata. Dapat
ditambahkan pula, karena tidak seperti para pembayar pajak, mereka yang membayar
zakat selain mendapat perhargaan di dunia (dihormati dan disayangi), mereka juga akan
mendapat ganjaran pahala di hari akhirat kelak. Hal ini, tentunya, akan lebih memotivasi
lagi kaum Muslimin untuk membayar zakat.
Zakat: Kebijakan Fiskal Ekonomi Islam
Kebijakan fiskal adalah merupakan salah satu instrumen penting dalam teori ekonomi
untuk mengatur ekonomi sebuah negara. Kebijakan ini, dalam ilmu ekonomi, sering
didefinisikan oleh para ahli ekonomi sebagai kebijakan ekonomi negara yang berkaitan
~ 67 ~
erat dengan pajak dan pembelanjaan negara dalam usaha untuk mewujudkan kestabilan
ekonomi.
Dibandingkan dengan kebijakan ekonomi konvensional, kalau tidak karena adanya
institusi zakat, pada prinsipnya, negara Islam memiliki instrumen kebijakan fiskal yang
sama dengan negara bukan Islam. Namun, penerapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal
dalam ekonomi Islam adalah sangat berbeda dengan kebijakan ekonomi konvensional.
Sebab, negara Islam memiliki sumber pendapatan yang unik, di samping sumber
pendapatan negara lainnya, yaitu zakat. Secara umum, instrumen kebijakan fiskal Islam
dapat disebutkan sebagai berikut:
1. Pajak
Meskipun terjadi perdebatan tentang kebiasaan memungut pajak dalam Islam, namun
sejauhmana pendapatan negara tidak mencukupi dari sumber lain dan terutama dalam
kondisi mendesak, maka hampir semua para ulama dan ahli ekonomi Muslim
kontemporer tidak melihat pemungutan pajak sebagai sesuatu yang bertentangan dengan
Islam.
2. Zakat
Institusi ini dimaksudkan untuk mentrasfer kekayaan dari orang kaya kepada orang
miskin sehingga, pada gilirannya, akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjamin
keseimbangan pendistribusian pendapatan dan kesejahteraan serta terjaminnya
ketersediaan kebutuhan pokok kaum miskin.
3. Pengeluaran Negara
Jumlah, waktu, dan penggunaan pembelanjaan negara yang diperuntukkan untuk
menstabilkan ekonomi negara juga termasuk sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam
ekonomi Islam.
~ 68 ~
Kenapa Zakat Dikatakan sebagai Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam?
Sebagaimana kita pahami bahwa karakteristik utama dari zakat, seperti nisab dan
kategori penerima zakat: fakir, miskin, mu'allaf, musafir, orang berhutang, amil,
fisabillah, dan untuk memerdekakan budak, (Lihat: Q. S. at-Taubah: 60) telah ditentukan
secara mutlak (Qath‟i) oleh syari‘at Islam. Ketentuan syari‘at ini tidak dapat dirubah dan
dimanipulasi sehingga menyebabkan zakat tereliminir untuk dapat dikategorikan sebagai
salah satu instrumen kebijakan ekonomi dalam Islam. Alasannya adalah karena kita
(negara) tidak mempunyai hak untuk memanipulasi ayat-ayat al-Qath‟i (bermakna
mutlak) yang mengatur tentang zakat. Walaupun demikian, ada beberapa faktor lain yang
memungkinkan institusi zakat dapat dikontrol atau disesuaikan dengan kebutuhan terkini
oleh negara dalam usaha untuk memberdayakan ekonomi umat.
Bagaimana cara zakat itu dikumpulkan dan didistribusikan? Berapa banyak komposisi
zakat yang dikumpulkan dalam bentuk uang atau barang, atau kombinasi dari keduanya?
Jawaban pertanyaan ini dapat ditentukan oleh pemerintah (penguasa), sejauhmana
prinsip-prinsip pengumpulan dan pendistribusian zakat tidak bertentangan dengan aturan
Ilahi dan nikmat zakat itu haruslah benar-banar dapar dirasakan secara optimal oleh para
penerima zakat. Dalam mensejahterakan ekonomi umat, pemerintah dapat
mengumpulkan dan mendistribusikan zakat pada masa yang paling tepat dalam tahun-
tahun tertentu demi kesejahteraan umat. Cara-cara ini telah pernah dipraktekkan
Rasulullah saw dan ke-empat Khulafa ar-Rasyidin-Nya. Dimana pada masa-masa tertentu
zakat tidak dibagi-bagikan pada tahun ia dikumpulkan, namun pendistribusiannya ditunda
dan dilakukan pada tahun-tahun selanjutnya sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat
pada waktu itu. Pendek kata, waktu pengumpulan dan pendistribusian zakat telah
memungkinkan negara untuk menyusun perencanaan kebijakan fiskal negara sebagai
suatu pendekatan untuk menyesuaikan perubahan struktural pendistribusian harta dalam
masyarakat.
Selanjutnya, dari segi kuantitas zakat yang berhasil dikumpulkan negara-negara Muslim,
persentase atau jumlah sumbangan sektor zakat terhadap pendapatan negara, GDP (Gross
~ 69 ~
Domestic Product), ternyata tidak bisa disepelekan. Ini dapat dilihat dari pengalaman
negara-negara, seperti Syria, Arab Saudi, dan Sudan dimana pendapatan negara yang
bersumber dari zakat adalah berkisar antara 1%-10% dari GDP. Alasan-alasan ini telah
memperkukuh institusi zakat sebagai salah satu instrumen penting kebijakan fiskal dalam
ekonomi Islam.
Tujuan Kebijakan Fiskal dalam Islam
Tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, sebenarnya, tidak jauh berbeda dengan
tujuan kebijakan fiskal versi ekonomi konvensional. Perbedaannya hanya lebih
disebabkan oleh prioritas dan esensi utama yang ingin dicapai. Tujuan umum yang ingin
dicapai kebijakan fiskal Islam, secara garis besar, adalah sebagai berikut: (1) untuk
mencapai pertumbuhan ekonomi yang konsisten dan kontinuitas dengan penggunaan
sumberdaya alam dan sumber daya manusia secara optimal; (2) untuk menjamin
pendistribusian pendapatan yang berkeadilan; (3) untuk menjaga stabilitas harga (inflasi)
barang dan jasa di pasar; (4) untuk menciptakan lapangan kerja baru; dan (5) untuk
memastikan pelaksanaan norma-norma keislaman, amar ma‟ruf wa nahi munkar dan
memprioritaskan aktivitas-aktivitas ekonomi yang mengarah kepada usaha-usaha untuk
mensejahterakan ekonomi umat.
Keberhasilan Kebijakan Fiskal Ditentukan oleh Kebijakan Ekonomi Lainnya
Semua tujuan kebijakan fiskal di atas, pada intinya, adalah dimaksudkan untuk
mewujudkan kesejahterakan ekonomi umat. Tidak seperti konsep kesejahteraan dalam
Islam, konsep kesejahteraan dalam ekonomi konvensional hanya terbatas dan terfokus
pada usaha untuk memaksimalkan keuntungan material semata tanpa mempertimbangkan
aspek spritual umat. Sebaliknya, Islam melihat kesejahteraan umat sebagai sesuatu yang
bersifat komprehensif meliputi kesejahteraan dunia dan akhirat. Inilah, sebenarnya,
tujuan utama setiap insan hidup di dunia ini, yaitu untuk mencapai falah (kemenangan)
baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mewujudkan tujuan suci ini, maka menurut Imam
al-Ghazali, zakat itu mesti diarahkan untuk mempromosikan kesejahteraan dan menjamin
~ 70 ~
terpeliharanya iman, kehidupan, intelektual, dan harta umat secara maksimal. Sementara
itu, Ibn Qayyim telah memasukkan keadilan yang hakiki, kebahagiaan, dan
kebijaksanaan (wisdom) sebagai unsur penting lainnya dari kesejehteraan umat yang
harus mendapat prioritas utama dari institusi zakat. Inilah perbedaan utama lainnya antara
sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional yang ―bebas nilai‖ (value-
free) dimana nilai-nilai moral tidak mendapat tempat dalam sistem ekonomi mereka.
Akan tetapi, perlu diingat bahwa untuk memberdayakan ekonomi kaum berpendapatan
rendah dan menstabilkan ekonomi negara secara signifikan, kebijakan fiskal tidaklah
memadai bila diregulasikan secara sendiri dan terpisah dari kebijakan-kebijakan ekonomi
lainnya. Oleh karena itu, kebijakan ini haruslah dilaksanakan bersama-sama secara
paralel dan simultan serta integratif dengan kebijakan moneter (monetary policy) dan
kebijakan-kebijakan ekonomi lainnya. Tentunya, keberhasilan zakat sebagai salah satu
instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam untuk memberdayakan ekonomi umat
sangat bergantung kepada sistem manajemen institusi zakat itu sendiri. Strategi
pendistribusian zakat, seperti pengalaman Malaysia, juga sangat menentukan berhasil
tidaknya ekonomi golongan papa diberdayakan.
Berdasarkan pengalaman Pusat Pungutan Zakat (PPZ), Jawatan Kuasa Baitulmal, Majlis
Agama Islam Wilayah Persekutuan dan Wilayah Selangor, Malaysia, cara yang sangat
efektif (jitu) untuk memberdayakan ekonomi para kaum dhu'afa adalah dengan cara
mendistribusikan zakat kepada mereka dengan cara memberikan modal usaha atau
menyediakan fasilitas-fasilitas ekonomi produktif, seperti mengusahakan pembukaan
bengkel, mesin jahit, pemberian modal untuk industri kecil keluarga, dan sebagainya.
Dalam penelitiannya terhadap beberapa responden (penerima zakat) di Wilayah Selangor
yang dilakukan akhir-akhir ini, Mohd. Ali Mohd. Noor (1999) menemukan bahwa hampir
setengah dari jumlah responden (penerima zakat) kini telah berhasil dalam usaha bisnis
yang dijalankan mereka yang dibiayai dengan modal zakat. Bahkan merekapun kini telah
menjadi pembayar zakat. Namun, keberhasilan ini, tentu saja, tidak terlepas dari sistem
~ 71 ~
manajemen dan pengawasan zakat profesional baik yang dijalankan oleh para amil yang
jujur, amanah dan bertanggung jawab.
Enggan Membayar Zakat, Bisa Dipaksa.
Seperti telah disebutkan di atas, tujuan utama yang ingin diwujudkan oleh zakat adalah
untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial dalam masyarakat. Hal ini seperti
disebutkan oleh Umer Chapra (1995) dengan mengutip dari apa yang telah ditegaskan
oleh Khalifah Umar bin Khattab yang berbunyi: "Bahwa setiap orang mempunyai hak
yang sama terhadap harta di dalam mesyarakat, tidak ada seorang pun, termasuk diri
saya (Umar ra) memiliki hak yang lebih besar terhadapnya daripada orang lain, dan
siapapun yang hidup lebih lama, dia akan melihat bahwa sungguhpun seorang
penggembala di bukit Sinai, ku (Umar ra) pastikan ianya akan menikmati bagiannya dari
harta itu". Selaras dengan perkataan Umar bin Khattab ra di atas, Ali bin Abi Thalib ra
juga menyebutkan bahwa: "Allah swt telah mewajibkan bagi orang kaya untuk
memberikan kaum miskin apa saja yang mencukupi bagi mereka, jika kaum miskin
kelaparan atau telanjang (tidak memiliki pakaian), itu karena mereka yang kaya telah
memeras mereka (dari hak mereka). Oleh karena itu adalah wajar bila hak orang miskin
tidak dipenuhi, maka Allah swt akan meminta pertanggungjawaban dan sekaligus
menghukum mereka (orang kaya)".
Tujuan berzakat ini, sebenarnya, telah dipertegas dengan jelas oleh Allah swt dalam al-
Qur‘an yang bermakna: ―Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu
kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka,
sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka....‖. (Q.S. At-
Taubah: 103). Selain ayat al-Qur'an di atas, banyak juga Hadist yang menjelaskan
persoalan yang sama dimana zakat hendaklah dikeluarkan oleh si kaya untuk
didistribusikan kepada si miskin. Kalaupun si kaya enggan mengeluarkan zakat, ayat di
atas menegaskan "ambillah" dari harta mereka. Ini bermakna bahwa dalam harta orang
kaya ada hak-hak orang miskin (zakat) yang bisa diambil secara paksa seandainya si kaya
menolak untuk menunaikan tanggung jawabnya. Hal ini seperti diungkapkan oleh ulama
~ 72 ~
kontemporer terkenal, Syeikh Yusuf Qardhawi, dalam kitab Fiqh az-Zakat-nya yang
menegaskan bahwa zakat hanya diwajibkan bagi si kaya untuk membantu si miskin,
namun bila mereka enggan mengeluarkan zakat, maka pihak berkuasa memiliki hak
untuk memaksanya. Upaya untuk memerangi umat yang ingkar membayar zakat ini dapat
kita rujuk pada tindakan Khalifah Abu Bakar as-Siddiq ra, beberapa hari setelah
kemangkatan Rasulullah saw, yang dikenal dengan Perang Siffin. Alasan utama kenapa
Khalifah pertama ini memerangi mereka adalah seperti kata beliau sendiri: "Demi Allah
aku akan memerangi mereka yang membedakan di antara sembahyang dan zakat karena
zakat adalah tuntutan terhadap harta. Demi Allah, seandainya mereka enggan membayar
zakat itu, sedangkan mereka pernah membayarnya kepada Rasulullah aku tetap akan
memerangi mereka." (H.R. Ibn Hajar dan Bukhari).
Zakat sebagai Penstabilisasi Ekonomi (Economic Stabilisator)
Selain berfungsi untuk menseimbangkan pemilikan harta antara si kaya dan si miskin,
menurut A. M Sadeq (1990) zakat juga dapat difungsikan sebagai instrumen kebijakan
untuk menstabilkan kondisi ekonomi yang stagnan dan berfluktuasi. Fungsi kebijakan ini,
diistilahkan dengan ―Counter-Cyclical Policy” (Kebijakan Kounter Siklus). Pada masa
resesi ekonomi yang ditandainya dengan sukarnya untuk menjual barang karena
terbatasnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat, maka negara dapat membeli
barang yang tidak terjual itu dengan menggunakan pendapatan yang bersumber dari zakat
untuk didistribusikan kepada mereka yang miskin (penerima zakat). Tindakan ini
dimaksudkan untuk menstimulasi peningkatan jumlah permintaan masyarakat miskin
tanpa terjadi mismanagement, korupsi, manipulasi dana zakat dan kebocoran (leakages)
pemungutan dan pendistribusian dana zakat lainnya.
Namun dalam membeli barang untuk didistribusikan kepada kaum miskin, hendaklah
dipastikan bahwa barang tersebut merupakan barang-barang kebutuhan pokok mereka.
Sebalikya, pada masa inflasi yang ditandainya dengan melimpah ruahnya uang yang
beredar dalam masyarakat, penundaan pendistribusian zakat adalah strategi jitu untuk
menstabilkan tingkat harga. Akan tetapi harus disadari bahwa kebijakan ini mempunyai
~ 73 ~
kelemahan tersendiri karena penundaan pendistribusian zakat justeru akan lebih
memudaratkan kaum miskin yang sedang memerlukan bantuan mendesak, apalagi
golongan miskin inilah yang sangat merasakan dampak negatif pada masa inflasi. Di
tengah berlangsungnya inflasi yang ditandai dengan mahalnya harga barang dan jasa,
golongan dhu‘afa akan mengalami kesukaran untuk memenuhi kebutuhan mereka karena
kenaikan harga barang di pasar tidak diimbangi oleh kenaikan jumlah pendapatan yang
mereka terima. Kalau hal ini berlaku, maka keseluruhan tujuan zakat akan ternodai akibat
penundaan pendistribusian zakat itu sendiri.
Ini tidak berarti kebijakan ini tidak memungkinkan untuk diadopsi dalam menstabilkan
ekonomi. Hanya pengadopsiannya saja yang perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi
pada masa dan tempat tertentu. Kebijakan ini, sebenarnya, bukanlah sesuatu persoalan
baru dalam ekonomi Islam, sebab kebijakan ini telah pernah dipraktekkan Rasulullah dan
ke-empat Khalifahnya lebih kurang 14 abad lalu. Pada situasi tertentu, zakat yang telah
dikumpulkan tidak langsung didistribusikan pada tahun tersebut melainkan ditunda
pendistribusian pada tahun berikutnya demi mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan
ekonomi umat pada umumnya dan keberadaan ekonomi golongan miskin dan papa
khususnya.
Dengan kata lain, cara pendistribusian zakat hendaklah disesuaikan dengan keadaan
ekonomi terkini. Pada saat inflasi, zakat itu hendaklah tidak dibayar atau dikurangi
pembayaran dalam bentuk uang atau barang konsumen (consumer goods), namun
hendaklah pembayaran zakat itu lebih banyak didistribusikan dalam bentuk barang
produsen (producer goods). Sebaliknya, jika ekonomi dalam keadaan deflasi, hendaklah
zakat itu lebih banyak dibayar dalam bentuk kas atau barang produsen, sementara itu
pembayaran dalam bentuk barang konsumen hendaklah dibatasi, kalau tidak bisa
dihindari samasekali. Bila cara pendistribusian zakat seperti dipaparkan di atas mampu
berfungsi maksimal, maka tidaklah salah bila zakat dapat dikatakan sebagai penstabilisasi
ekonomi (economic stabilator) umat.
~ 74 ~
Walaupun demikian, ada dua keraguan yang mungkin timbul dalam konteks ini, yaitu:
Pertama, pola konsumsi umat Islam yang sederhana akan menyebabkan zakat tidak dapat
difungsikan secara maksimal untuk meningkatkan konsumsi dan permintaan masyarakat
golongan berpendapatan rendah terhadap barang. Kedua, pendistribusian zakat justeru
akan meningkatkan inflasi, jika ianya dimaksudkan untuk meningkatkan permintaan
efektif masyarakat terhadap barang.
Sebenarnya, kedua keraguan ini tidak cukup beralasan untuk ditakuti. Sebab anjuran
agama agar mengkonsumsi barang secara sederhana tidaklah berguna bagi orang miskin,
karena pada prinsipnya mereka belum terpenuhi kebutuhan pokok mereka.
Kesederhanaan dalam berkonsumsi hanya dibatasi bagi orang kaya terutama terhadap
barang-barang mewah, dan bukan bagi para penerima zakat yang memang belum cukup
memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, apalagi untuk berfoya-foya.
Ini dengan sendirinya akan mendorong para investor untuk menginvestasikan modal
mereka pada sektor-sektor yang menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa untuk
mengimbangi kenaikan kebutuhan masyarakat miskin (kebutuhan pokok). Ketersediaan
barang kebutuhan pokok yang mencukupi akibat munculnya industri baru, maka dengan
otomatis harga barang kebutuhan pokok akan lebih stabil dan terjangkau.
Selanjutnya, keraguan kedua dimana zakat akan mengakibatkan naiknya tingkat inflasi,
juga merupakan keraguan yang tidak beralasan. Sebagaimana dipahami bahwa inflasi itu
terjadi apabila jumlah uang yang beredar dalam masyarakat cukup banyak, sementara itu
jumlah barang dan jasa yang tersedia di pasar adalah terbatas. Pendistribusian zakat akan
meningkatkan daya beli para penerima zakat terutama terhadap barang-barang kebutuhan
pokok. Kenaikan harga barang kebutuhan pokok akibat meningkatnya permintaan
masyarakat tidak akan terjadi sebab para investor telah terdorong untuk menanamkan
modal mereka di sektor-sektor yang menghasilkan barang-barang kebutuhan pokok
sehingga secara otomatis jumlah penawaran terhadap kebutuhan pokok akan meningkat
pula. Dengan demikian memperjelas bahwa kenaikan harga di sektor ini tidak akan
~ 75 ~
mempengaruhi permintaan barang di sektor-sektor lainnya, dan berarti skenario ini tidak
akan menimbulkan inflasi.
Walaupun keterbatasan zakat dalam menstabilkan ekonomi seperti disebutkan di atas,
karena fungsi zakat adalah lebih diutamakan untuk merapatkan jurang pendapatan
(income gap) antara si kaya dan si miskin, namun zakat tetap akan mendorong
pertumbuhan ekonomi umat dengan alasan-alasan berikut ini:
1. Zakat merupakan hukuman terhadap praktek monopoli dan menelantarkan kas yang
tidak produktif (idle cash). Karena zakat terhadap harta-harta yang sudah sampai
nisab harus senantiasa dibayar pada persentase yang telah ditentukan. Pembayaran
zakat terhadap kas yang tidak produktif, dengan sendirinya, secara perlahan-lahan
akan mengurangi jumlah kas yang tersedia. Dalam hal ini zakat telah berfungsi
sebagai disinsentif untuk membiarkan kas disimpan tidak produktif. Dengan kata lain,
disinsentif untuk membiarkan kas tidak produktif adalah merupakan insentif yang
mendorong umat Islam untuk menginvestasikan kas atau uang mereka di sektor-
sektor bisnis yang produktif.
2. Pendistribusian zakat kepada golongan miskin, dengan sendirinya, akan
meningkatkan standar hidup, kesehatan, pendidikan dan skill serta produktivitas para
penerima zakat (muzakki). Ini, pada gilirannya, secara gradual tapi pasti, akan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.
3. Pendistribusian zakat kepada mereka yang berhak menerimanya jelas akan
meningkatkan daya beli (purchasing power) mereka, terutama terhadap barang-
barang kebutuhan pokok. Peluang ini tentu menarik para investor untuk
menginvestasikan modal mereka di sektor-sektor yang memproduksikan barang-
barang kebutuhan pokok. Hal ini tentu saja, akan mewujudkan kestabilan harga,
membuka peluang kerja baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang
menjanjikan (promising economic growth).
~ 76 ~
Pengaruh Zakat terhadap Ekonomi
Setelah melihat peran zakat terhadap perekonomian umat secara umum di atas, sekarang
marilah kita lihat pengaruh zakat secara lebih terperinci terhadap Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN), produktivitas kerja, dan penciptaan lapangan kerja baru.
Pengaruh Zakat terhadap APBN
Setelah perang dunia ke-II berakhir, konsep kesejahteraan ekonomi umat telah menjadi
trend dan prioritas penting negara. Oleh karena itu, banyak negara yang telah
mengalokasikan biaya-biaya tertentu ke dalam pos APBN sebagai salah satu usaha untuk
memberdayakan kaum miskin dan mengentaskan kemiskinan, khususnya bagi mereka
yang tergolong ke dalam kategori ―muzakki‖ (penerima zakat). Dengan adanya institusi
zakat, maka dana APBN yang seharusnya dialokasikan untuk mensejahterakan kaum
dhu'afa, kini telah dapat dibiayai dari dana yang bersumber dari zakat. Karenanya, dalam
melihat sejauhmana pengaruh zakat terhadap APBN, dapat dijelaskan dari sejauhmana
sumber dana yang berasal dari zakat dapat didistribusikan untuk meningkatkan standar
hidup para penerima zakat. Hal ini dengan sendirinya berimplikasi bahwa jumlah dana
APBN yang sepatutnya digunakan untuk membantu fakir miskin telah ditutupi oleh dana
yang dikumpulkan dari zakat. Sehingga dana APBN yang diperuntukkan dan
dialokasikan untuk memberdayakan golongan miskin tersebut, akan bermanfaat untuk
membangun infrastruktur ekonomi lainnya sehingga dapat mendongkrak pertumbuhan
ekonomi negara.
Walaupun demikian, untuk merealisasikan tujuan ini hendaklah zakat dikelola dengan
sistem administrasi dan manajemen zakat yang efisien, efektif, dan profesional serta
berada di bawah pengawasan orang-orang yang amanah, adil, jujur, dan bertanggung
jawab baik terhadap umat maupun kepada Allah Sang Pencipta. Begitu juga dengan biaya
administrasi zakat, hendaklah tidak dipungut melebihi dari 1,25% atau 1/8 dari dana
zakat yang dikumpulkan. Bila semua ketentuan ini dapat dipenuhi, maka dengan mudah
~ 77 ~
zakat itu akan bisa didistribusikan untuk para dhu'afa yang memang sangat
memerlukannya.
Pengaruh Zakat terhadap Produktivitas
Sebagaimana disetujui oleh mayoritas para fuqaha, tujuan zakat adalah untuk
meningkatkan standar hidup para dhu'afa dengan memberikan hak kepada mereka untuk
memiliki apa yang berhak mereka terima dari orang kaya. Artinya bahwa zakat haruslah
dibayar secara langsung kepada mereka agar dapat segera digunakan baik dalam
usahanya untuk memenuhi kebutuhan pokok harian maupun digunakan sebagai modal
untuk menjalankan bisnis mereka. Kenaikan pendapatan para dhu'afa akibat menerima
zakat, secara otomatis, akan meningkatkan kemampuan mereka untuk mengkonsumsikan
barang-barang dan jasa-jasa yang di jual di pasar. Pendapatan yang diterima dari hasil
zakat juga akan memberi kesempatan bagi kaum miskin untuk menggunakan fasilitas
sekolah serta memperbaiki pola makanan dan kesehatan mereka. Semua kesempatan ini,
tentunya, akan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Pemberdayaan ini, seperti
dibuktikan oleh riset ilmiah adalah merupakan faktor-faktor penting yang sangat
mempengaruhi produktivitas kerja. Singkatnya, pemenuhan kebutuhan pokok para
pekerja, terutama orang-orang dhaif (para penerima zakat) dengan sendirinya akan
mampu meningkatkan produktivitas kerja mereka.
Peningkatan produktivitas kerja para dhu'afa bisa jadi disebabkan oleh dua kemungkinan
berikut, yaitu: Pertama, peningkatan jumlah kontribusi para pekerja baik dalam bentuk
jumlah jam kerja maupun dalam bentuk jumlah hari kerja sebagai akibat perbaikan gizi
para pekerja, dan kedua, peningkatan produktivitas para pekerja akibat membaiknya
kesehatan fisik, psikologi, dan kemampuan spritual para pekerja, yang dalam ilmu
ekonomi sering disebut dengan intensitas kerja per jam (working intensity per-hour).
~ 78 ~
Pengaruh Zakat terhadap Peluang Kerja
Kaitannya dengan peluang kerja, kehadiran institusi zakat, sekurang-kurangnya, akan
menciptakan dua peluang kerja baru, yaitu: Pertama, peningkatan kesempatan kerja
untuk mengelola administrasi zakat (amil) mulai dari para pekerja pengumpul zakat
(collector), pengurus (administer), dan pendistribusi (distributor) zakat kepada mereka
yang berhak menerimanya dan kedua, pendistribusian zakat, seperti disebutkan terdahulu,
akan menyebabkan naiknya jumlah permintaan terhadap barang-barang kebutuhan pokok
oleh para dhu'afa, sehingga akan mendorong tumbuhnya industri-industri baru yang
memproduksi barang-barang kebutuhan pokok tersebut. Lahirnya industri-industri baru
ini akan membuka lapangan kerja baru yang dapat segera diisi oleh golongan masyarakat
berpendapatan rendah yang umumnya masih berstatus pengangguran.
Maka dengan adanya peluang kerja baru ini, otomatis akan lebih mempercepat terjadinya
proses keadilan dalam ekonomi umat yang ditandai dengan semakin mengecilnya jurang
pemisah (pendapatan) antara si kaya dan si miskin. Artinya apa yang ditakutkan oleh
kebanyakan orang dimana orang yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan
semakin papa tidak akan berlaku. Berdasarkan studi simulasi statis (static simulation
study) yang dilakukan untuk mengetahui perbandingan pengaruh zakat terhadap jurang
pemisah ini, Monzer Kahf (1989) dalam risetnya mendapati bahwa dalam masa sepuluh
tahun jurang pemisah antara si kaya dan si miskin di beberapa negara Muslim telah
berkurang drastis dari 9 poin menjadi 6,15 poin. Sementara itu, Anas Zarqa (1995) telah
menemukan bahwa jumlah pendapatan 10% kaum miskin yang hidup di beberapa negara
Islam, telah bertambah dua kali lipat sebagai konsekuensi positif pengdistribusian zakat
dari si kaya kepada si miskin.
Kesimpulan
Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bagaimana signifikan, sebenarnya, peran dan
pengaruh zakat dalam mensejahterakan ekonomi umat. Zakat tidak hanya berfungsi untuk
membantu memenuhi kebutuhan pokok kaum dhu'afa, tetapi lebih dari pada itu, zakat
~ 79 ~
berfungsi ganda (multi-fungsi) dalam mengangkat harkat dan martabat ekonomi umat.
Zakat sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal dalam Islam, juga dapat berfungsi
untuk menstabilkan ekonomi dan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi umat.
Ilustrasi-ilustrasi di atas memberikan gambaran bahwa tidak mustahil bila institusi zakat
dikelola dengan efektif, efisien dan profesional oleh amil-amil yang amanah, adil, jujur,
dan bertanggung jawab, maka umat Islam dengan mudah akan dapat keluar dari
perangkap kemiskinan (poverty trap).
Hal ini seperti pernah dibuktikan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dimana
dengan sistem pengelolaan zakat yang baik serta didukung oleh kesadaran umat Islam
yang tinggi terhadap tanggung jawabnya untuk membayar zakat, maka tidaklah
berlebihan bila pada masa tersebut sang Khalifah mengalami kesukaran untuk mencari
orang yang mau dan patut menerima zakat. Semua orang pada masa tersebut sudah hidup
dalam suasana makmur dan sejahtera sehingga dana zakat yang terkumpulkan tidak ada
lagi yang mau menerimanya. Namun permasalahannya sekarang, kenapa Umar bin Abdul
Aziz bisa melakukan demikian, dan kenapa kita tidak? Apakah karena kita yang hidup di
akhir zaman sekarang tidak lagi berpegang teguh pada pedoman yang sama dengan Umar
bin Abdul Aziz? Mari kita ber-muhasabah (intropeksi) diri dan mulai mengatur derap
langkah ke depan dengan penuh perencanaan dengan bercermin pada pengajaran sejarah
silam Islam dan kemudian diadopsi serta dimodifikasi sesuai dengan kondisi terkini.
Tidak salah bila sistem pengelolaan zakat yang telah berhasil dipraktekkan di negara jiran
Malaysia dan negara-negara Muslim lainnya kita iktibari dan kemudian kita jadikan
masukan berharga untuk memanej institusi zakat secara profesional dan penuh tanggung
jawab di negara tercinta kita, InsyaAllah.
~ 80 ~
BIBLIOGRAFI
Ahmad, Khurshid. 1979. ―Economic Development in an Islamic Framework‖, dalam
Khurshid Ahmad (ed). Islamic Perpectives. Leicester: The Islamic
Foundation.
Akhtar, Ramzan. 1993. ―Modelling the Economic Growth of An Islamic Economy‖. The
American Journal of Islamic Social Science (AJISS). 10(1): 56-87.
al-Faridi, F. R. 1980. ―Zakat and Fiscal Policy‖, dalam Khurshid Ahmad (ed). Studies in
Islamic Economics. Great Britain: Redwood Barn Limited, Trowbridge and
Esher.
__________. 1993. Aspects of Islamic Economics and the Economy of Indian Muslim.
al-Ghazali, Muhammad. 1952. al-Islam wa al-Awda‟ al-Iqtisadiyyah. Cairo: Dar al-Kitab
al-‗Arabi.
al-Jammal, Muhammad Abdul Mun‘im. 2000. ―Ensiklopedia Ekonomi Islam‖, (terj)
Salahuddin Abdullah. Mausu‟at al-Iqtisad al-Islami. Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka (DBP).
al-Khaibawi. 1989. ―Durratun Nasihin‖, (terj) Syamsudin Manap. Butir-Butir Nasehat.
Kuala Lumpur: Victory Agencie.
al-Mubarak, Muhammad. 1972. Nizam al-Islam al-Iqtisadi: Mabadi wa Qawa‟id
„Ammah. Beirut: Dar al-Fikr.
al-Qur‟an dan Terjemahan. 1974. Menteri Agama Republik Indonesia.
Ariff, Mohamed. 1982. ―Monetary and Fiscal Economics of Islam‖, dalam Arif, M. (ed).
Monetary and Fiscal Economics of Islam. King Abdul Aziz, Jeddah:
International Centre for Research in Islamic Economics.
Arif, Muhammad, 1983. "Towards Establishing the Micro foundations of Islamic
Economics: AContribution to the Theory of Consumer Behaviour in an
Islamic Society". A paper presented at the 12th Annual Conference of the
Association of Muslim Social Scientists, University of Illinois, Urbana
Champagn.
Awdah, Abd al-Qadir. 1977. Al-Mal wa al-Hukm fi al-Islam. 5th
Edition. Cairo: al-
Mukhtar al-Islami.
Chapra, M. Umer. 1985. Towards a Just Monetary System, Leicester, UK: The Islamic
Foundation.
~ 81 ~
__________. 1992. Islam and the Economic Challenge. Herdon, USA: The International
Institute of Islamic Thought and The Islamic Foundation.
__________. 1993. Islam and Economic Development: A Strategy for Development with
Justice and Stability. Islamabad: International Institute of Islamic Thought and
Islamic Research Institute.
__________. The Islamic Welfare State and Its Role in Economy. Leicester, UK: The
Islamic Foundation.
Denison, Edward F. 1967. Why Growth Rates Differ. Washington, D. C.: The Brookings
Institution.
__________.1985. Trends in American Economic Growth, 1929-1982. Washington,
D.C.: The Brookings Institution.
Domar, Evsey D. 1946. ―Capital Expansion, Rate of Growth, and Employment‖.
Econometrica. 14: 137-147. Reprinted in Stiglitz and Uzawa (1969).
Haneef, Mohamed Aslam Mohammed. 1997. ―Islam: The Islamic Worldview and Islamic
Economics‖. IIUM Journal of Economics & Management. 5(1): 39-65.
Harrod, R. F. 1939. ―An Essay in Dynamic Theory‖. Economic Journal. 49: 14-33.
Reprinted in Stglitz and Uzawa (1969).
Hassan, Zubair. 1988. ―Distributional Equity in Islam‖, dalam Munawar Iqbal (ed).
Distributive Justice and Need Fulfilment in An Islamic Economy. Leicester,
UK: The Islamic Foundation.
Hassan, Zubair and Muhammad Arif. 1990. "The Basic Needs Fulfillment Guarantee in
Islam and A Measure of Its Financial Dimension in Selected Muslim
Countries". Journal of Islamic Economics. 1(3): 2-23.
Husaini, Sayyid Abdul Qadir. 1966. Arab Administration. Lahore: Sh. Muhammad
Ashraf.
Hassanuzzaman, S.M. 1984. ―Definition of Islamic Economics". Journal of Research in
Islamic Economics, Vol. 1, No. 2.
Ibn Khaldun. 1993. ―Mukadimah Ibnu Khaldun‖, (terj) Muqaddimah. Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP).
Imam Nawawi. 2000. ―Riyadhus Salihin. Jilid 1‖, (terj) M. Ardai Rathomy. Taman
Orang-orang Salih. Singapura: Pustaka Nasional PTE. Ltd.
~ 82 ~
__________. 2000. ―Riyadhus Salihin. Jilid 2‖, (terj) M. Ardai Rathomy. Taman Orang-
orang Salih. Singapura: Pustaka Nasional PTE. Ltd.
Iqbal, Munawar. 1985. ―Moderation and Aggregate Consumption in an Islamic
Economy‖. Journal of Research in Islamic Economy. 3(1): 45-60.
James Tobin. 1980. ―Stabilization Policy Ten Years After‖. Brookings Papers on
Economic Activity. 1: 19-71.
Kahf, Monzer. 1992. ―Saving and Investment Function in Two-Sector Islamic Economy‖,
dalam Sadeq, AbulHasan, M, (ed). Financing Economic Development: Islamic
and Mainstream Approaches”. Kuala Lumpur: Longman Malaysia.
__________. 1997. ―Potential Effects of Zakat on Government Budget‖. IIUM Journal of
Economics & Management. 5(1): 67-85.
Kamali, Mohammad Hasyim. 1989. Principles of Islamic Jurisprudence. Petaling Jaya,
Kuala Lumpur: Pelanduk Publication.
Karl Marx. 1987. Das Kapital, (terj) S. Moore and E. Avehing. 3rd
Edition. London: F.
Engels.
Keynes, John Maynard. 1936. The General Theory of Employment, Interest and Money.
London: Macmillan.
Khan, Muhammad Akram. 1983. Issues in Islamic Economics, Lahore: Islamic
Publications Ltd.
__________. 1984. "Islamic Economics: Nature and Need". Journal of Research in
Islamic Economics. Vol. 1, No. 2.
__________. 1989. Economic Teachings of Prophet Muhammad: A Select Anthology of
Hadith Literature on Economics. Islamabad: International Institute of Islamic
Economics and Institute Policy Studies.
__________. 1994. An Introduction to Islamic Economics. Pakistan: The International
Institute of Islamic Thought and Institute of Policy Studies.
__________. 1994. Economics of the Quran: A Study of Sura al-Maida & Sura al-Mulk.
Lahore: Library & Information Management Academy.
Lucas, Robert E., Jr. 1988. ―On Mechanics of Economic Development‖. Journal of
Monetary Economics. 22: 3-42.
Mankiw, N. Gregory, Romer, David, and Weil, David N. 1992. ―A Contribution to the
Empirics of Economic Growth‖. Quarterly Journal of Economics. 107: 407-437.
~ 83 ~
Mannan, M. A. 1988. ―The Economics of Poverty in Islam with Special Reference to
Muslim Countries‖, dalam Munawar Iqbal (ed). Distributive Justice and Need
Fulfilment in an Islamic Economy. Leicester, UK: The Islamic Foundation.
__________. 1989. Economic Development and Social Peace in Islam. London: Taha
Publisher.
Naqvi, S. N. H. 1982. ―Interest Rate and Inter-temporal Allocative Efficiency in an
Islamic Economy‖, dalam Ariff, M. (ed). Monetary and Fiscal Economics of
Islam. King Abdul Aziz, Jeddah: International Centre for Research in Islamic
Economics.
__________. 2000. ―International Economics and Trade Liberalization: Challenges to
Muslim Countries‖, makalah dipresentasikan pada International Conference.
Kuala Lumpur, Malaysia.
Naziruddin Abdullah dan M. Shabri Abd. Majid. 2001. ―Saving Behaviour in Islamic
Framework: The Case of International Islamic University, Malaysia‖. Jurnal
Syari‟ah. 9(2): 61-84.
__________. 2002. ―The Influence of Religiosity, Income and Consumption on Saving
Behavior: The Case of International Islamic University, Malaysia‖. Proceedings.
Simposium Nasional I Sistem Ekonomi Islami, UII Yogyakarta, 13-14 Maret.
Qardhawi, Yusuf. 1969. Fiqh al-Zakat. Beirut: Dar al-Irshad.
__________. 1997. ―Peran Nilai dan Moral Dalam Islam‖, (trans.) Hafidhuddin, Didin et
al. Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islam, Jakarta: Rabbani Press.
Romer, David. 1996. Advanced Macroeconomics. New York: The McGraw-Hill
Companies, Inc.
Sadeq, AbulHasan, M. 1980. "Distribution of Wealth in Islam", dalam K. T. Hussain et
al. (ed). Thought on Islamic Economics. Dhaka: Islamic Economics Research
Bureau.
__________. 1990. Economic Development in Islam. Kuala Lumpur: Pelanduk
Publication.
__________. 1992. ―Development Finance in an Islamic Economy: Domestic Sources‖,
dalam Sadeq, AbulHasan, M (ed). Financing Economic Development: Islamic
and Mainstream Approaches. Kuala Lumpur: Longman Malaysia.
Saiful Azhar Roesly. 2000. ―The Process of Choice According to Islam‖. Sun. March 25.
~ 84 ~
Sattar, M. Abdus. 1980. Ibn Khaldun's Contribution to Economic Thought. USA:
American Trust Publication.
Schumpeter, J. A. 1972. History of Economic Analysis. New York: McGraw-Hill Book.
Co. Inc.
Solow, Robert M. 1956. ―A Contribution to the Theory of Economic Growth‖. Quarterly
Journal of Economics. 70: 69-94. Reprinted in Stiglitz and Uzawa (1969).
Sutcliffe, Claud R. 1975. ―Is Islam an Obstacle to Development? Ideal Patterns of Belief
versus Actual Patterns of Behaviour‖. Jounal of Developing Areas. 10: 77-81.
Ul-Haq, Irfan. 1996. Economic Doctrines of Islam: A Study in the Doctrine of Islam and
Their Implications for Poverty, Employment and Economic Growth. Herdon,
Virginia, USA: The International Institute of Islamic Thought.
Yong, Alwyn. 1994. ―The Tyranny of Numbers: Confronting the Statistical Reality of the
East Asian Growth Experience‖. National Bureau of Economic Research
Working Paper, No. 4680.
Webster‘s International Dictionary
Yusuf, S. M. 1971. Economic Justice in Islam. Lahore: Sh. Muhammad Ashraf.
Zarqa, Muhammad Anas. 1988. ―Islamic Distributive Schemes‖, dalam Munawar Iqbal
(ed). Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy. Leicester,
UK: The Islamic Foundation.