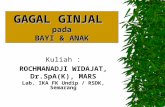5 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Tentang Ginjal 2.1 ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of 5 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Tentang Ginjal 2.1 ...
5
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Tentang Ginjal
2.1.1 Struktur dan Anatomi Ginjal
Ginjal merupakan sepasang organ vital manusia yang memiliki bentuk
seperti kacang, dua ginjal tersebut terletak di posterior perut dan dirongga luar
peritoneum. Karena posisinya yang berada di posterior dari peritoneum rongga
perut maka ginjal disebut sebagai organ retroperitoneum ( retro = di belakang).
2.1.2 Anatomi Eksternal Ginjal
Ginjal orang dewasa umumnya memiliki panjang 10-12 cm (4 -5 in), lebar 5
– 7 cm (2-3 in) dan tebal 3 cm (1 in) dan memilik berat sekitar 150 gram (Tortora
J,2014). Ginjal memiliki batas media cekung dimana terdapat hillus yang
merupakan tempat saraf masuk, ureter keluar, dan pembuluh darah dan getah
bening masuk dan keluar, dan batas lateral cembung. Dua permukaan ginjal
tersebut memiliki lapisan yang berfungsi sebagai lapisan luar yaitu kapsul fibrous
yang tipis (Hall, 2016).
Gambar 2. 1 Penampang melintang ginjal (a), piramida ginjal (b) dan nefron (c)
(Shier, 2012)
6
2.1.3 Anatomi Internal Ginjal
Potongan frontal ginjal memperlihatkan dua region berbeda yaitu daerah
superfisial berwarna merah muda yang dinamakan korteks ginjal dan bagian lebih
dalam yang berwarna coklat merah gelap disebut medulla ginjal (Tortora J, 2014).
Penampilan granular disebabkan oleh banyaknya glomeruli pada korteks. Medula
terdiri dari bagian dalam ginjal. Medula terdiri dari bagian luar dan sebuah bagian
dalam. Bagian luar memiliki penampilan lurik yaitu karena banyak tubulus
berjalan dari korteks ke bawah ke dalam medulla (gambar 2.1). Tubulus ini adalah
bagian dari nefron, unit fungsional ginjal, dan tubulus mengumpulkan ke dalam
struktur yang disebut piramida ginjal (Feher, 2017). Medula terbagi antara 8 – 10
massa jaringan bernetuk kerucut yang disebut pyramid ginjal. Setiap pyramid
ginjal merupakan perbatasan antara medula dan korteks yang berakhir di papilla
yang menghubungkan ke dalam ruang ginjal panggul (Hall, 2016) .
2.1.3.1 Struktur Makroskopik Ginjal
Nefron adalah unit fungsional ginjal dengan jumlah pada setiap manusia
sekitar 800.000 hingga 1.000.000 nefron yang masing-masing mampu
membentuk urin. Namun, ginjal tidak dapat meregenerasi nefron baru. Nefron
terdiri dari dua bagian yaitu : korpuskulum (badan kecil) ginjal tempat plasma
darah disaring dan tubulus ginjal yang dalamnya mengalir cairan yang telah
difiltrasi.
2.1.3.2 Korpuskulum Ginjal
a. Glomerulus
Glomerulus adalah seperti bola kapiler yang dikelilingi oleh cawan
epitel berdinding rangkap (Tortora, 2014). Glomerulus berisi jaringan
percabangan dan kapiler glomerulus anastomosis yang, dibandingkan
dengan kapiler lain, memiliki tekanan hidrostatik tinggi (sekitar 60 mm
Hg) (Hall, 2016).
b. Kapsul Bowman
Kapsul glomerulus (bowman) terdiri atas lapisan visceral dan parietal.
Lapisan visceral terdiri dari sel epitel skuamosa sederhana termodifikasi
atau yang disebut podosit. Terdapat dinding dalam kapsul yang
7
tersususn dari tonjolan-tonjolan beberbentuk kaki dari sel podosit yang
melingkari selapis sel endotel kapiler glomerulus. Cairan yang disaring
dari glomerulus masuk ke kapsul bowman, ruang anatara dua lapisan
kapsul bowman disebut lumesn saluran urin (Tortora, 2014).
2.1.3.3 Tubulus Ginjal
a. Tubulus Kontortus Proksimal
Tubulus kontortus proksimalis menunjukkan bagian dari tubulus yang
menyatu atau melekat ke kapsul glomerulus. Kontortus berarti tubulus
tersebut berbentuk bergulung rapat dan tidak lurus. Tubulus ini terletak
di korteks ginjal. Reabsoprsi terbesar zat terlarut dan air berlangung
pada tubulus ini dengan mereabsorpsi 65% dari air, Na+, dan K
+ yang
terfiltrasi 100% (Gambar 2.2.) (Tortora, 2014).
b. Lengkung Henle
Bentuk tajam berbentuk U atau jepit rambut loop yang masuk ke
medula ginjal (Sherwood, 2016). Disetiap nefron lengkung henle
sebagai penghubung tubulus kontortus prosimalis dan distalis. Bagian
pertama dari lengkung henle yang bernama pars desendens ansa henle
masuk ke dalam medula ginjal kemudian membelok tajam dan kembali
ke korteks ginjal sebagia pars asendens ansa henle. Lumen pars
asendens tipis sama seperti di bagian-bagian lain tubulus ginjal, hanya
epitelnya yang lebih tipis. Nefron dengan lengkung henle panjang
memungkinkan ginjal mengekskresikan urin yang sangat encer atau
sangat pekat (Gambar 2.2.) (Tortora, 2014).
c. Tubulus Kontortus Distal
Saat cairan mencapai ujung tubulus kontortus distalis 90-95% zat
teralarut dan air yang terfiltrasi telah dikembalikan ke dalam darah.
Tubulus distal terdiri atas bagian lurus yang tebal menanjak dari
lengkung henle kembali ke korteks (Mescher, 2013).
8
Gambar 2. 2 Bagian Nefron (Hall, 2016)
2.1.4 Fungsi Ginjal
Ginjal memiliki beberapa fungsi penting dalam tubuh manusia salah satunya
yaitu mengeksresikan sisa metabolisme dalam tubuh, namun masih ada beberapa
fungsi penting lainnya, diantaranya adalah :
2.1.4.1 Mengeksresikan Sisa Metabolisme Tubuh
Ginjal memiliki fungsi utama untuk menghilangkan sisa metabolisme yang
tidak dibutuhkan kembali oleh tubuh. Sisa metabolisme ini termasuk urea (dari
metabolism asam amino), kreatinin (dari keratin otot), asam urat (dari asam
nukleat), produk akhir dari kerusakan hemoglobin (seperti bilirubin) dan berbagai
metabolit hormone. Sisa metabolism tersebut harus dihilangkan tubuh secepat
mereka diproduksi. Selain itu, ginjal juga mengeksresikan sebagian besar racun
dan zat asing lainnya baik diproduksi oleh tubuh atau dicerna seperti pestisida,
obat-obatan dan zat aditif makanan (Hall, 2016).
2.1.4.2 Pengaturan Keseimbangan Asam-Basa
Ginjal dalam mempertahankan keseimbangan asam-basa yaitu melalui
pengeluaran urin yang asam atau basa. Pengeluaran urin asam akan mengurangi
jumlah asam dalam cairan ekstraselular, sedangkan urin basa akan mengurangi
jumlah basa dalam cairan ekstraseluler. Perubahan pH dapat memberikan
pengaruh terhadap beberapa organ tubuh. Keseimbangan asam-basa terkait
9
dengan pengaturan konsentrasi ion hidrogen bebas dalam cairan tubuh.
Konsentrasi ion hidrogen sangat mempengaruhi proses metabolisme yang
berlangsung dalam tubuh karena hampir semua aktivitas enzim dipengaruhi oleh
konsentrasi ion hydrogen (Jauharany dan Widyastuti, 2017).
Ginjal dalam mempertahankan pH darah agar tetap normal (7,4), darah
harus menyangga dan membuang kelebihan asam yang dibentuk oleh asupan
makanan dan metabolism tubuh. Ion bikarbonat mempengaruhi kapasitas dapar
darah, ion bikarbonat mudah disaring oleh glomerulus dan harus cepat
dikembalikan ke darah untuk mempertahankan pH yang tepat. Sekresi ion
hidrogen oleh tubulus ginjal dalam filtrate mencegah bikarbonat diekresikan ke
dalam urin dan menyebabkan kembalinya ion bikarbonat ke dalam plasma
(Strasinger, 2014).
2.1.4.3 Produksi Hormon
a. Eritropoietin
Selain fungsi utamanya mengatur volume dan komposisi plasma, dan
karenanya berkontribusi pada homeostasis semua cairan tubuh, ginjal
melakukan fungsi-fungsi penting lainnya. Ini termasuk sekresi
erythropoietin sebagai respons terhadap hipoksia. Erythropoietin
adalah hormon glikoprotein yang merangsang laju pembentukan sel
darah merah atau erythropoiesis. Ini membentuk loop umpan balik
negatif lain: pasokan oksigen yang buruk ke ginjal menstimulasi
sekresi erythropoietin, yang merangsang pembentukan sel darah merah
yang pada gilirannya meningkatkan pasokan oksigen ke ginjal (Feher,
2017).
b. Vitamin D
Vitamin D disintesis di kulit dan kemudian dikenakan untuk dua reaksi
hidroksilasi. Yang pertama terjadi di hati dan menghasilkan 25-OH-
cholecalciferol. Kedua Reaksi hidroksilasi terjadi pada mitokondria
ginjal sel tubulus proksimal dan menghasilkan 1,25-(OH)2
cholecalciferol, bentuk sirkulasi aktif vitamin D. Reaksi hidroksilasi di
ginjal dirangsang oleh hormon paratiroid, PTH, dan dengan plasma
10
rendah [Pi]. 1,25- (OH) 2 cholecalciferol menstimulasi Ca2 dan Pi
penyerapan dari usus dan membantu menjaga plasma [Ca2] dan [Pi]
dengan aksi pada tulang dan ginjal. Reaksi hidroksilasi ginjal sangat
penting untuk aktivitas vitamin D dan membentuk bagian dari umpan
balik negatifloop yang mengontrol homeostasis dari Ca2 dan fosfat
(Feher, 2017).
c. Renin
Renin angiotensin aldosterone sistem. Renin adalah enzim yang
disekresikan oleh sel granul di arteriol aferen sebagai respons terhadap
aferen yang lebih rendah tekanan arteriolar. Renin dapat mengubah
protein plasma precursor yang dibuat di hati menjadi untuk angiotensin
I, Angiotensin I lalu dikonversi menjadi angiotensin II oleh ACE,
terutama yang terletak di paru-paru. Angiotensin II memiliki dua
fungsi yaitu vasokonstriktor (meningkatkan total resistensi perifer,
sehingga cenderung mengembalikan tekanan darah menuju normal)
kuat dan melepaskan aldosteron dari korteks adrenal. Peningkatan
aldosteron yang bersirkulasi memiliki efek mengurangi ekskresi Na+
dan meningkatkan ekskresi K+. Hasilnya adalah kecenderungan untuk
mempertahankan ekstraseluler volume, dengan demikian
mempertahankan terhadap penurunan tekanan darah (Feher, 2017).
2.2 Tinjauan Tentang Penyakit Ginjal Kronik
2.2.1 Definisi Penyakit Ginjal Kronik
Penyakit ginjal kronik merupakan penyakit yang menahun dan bersifat
progresif, pada pasien penyakit ginjal kronik kemampuan tubuh gagal untuk
mempertahankan metabolisme atau keseimbangan cairan dan elektrolit,
menyebabkan uremia. Penyakit ginjal kronik terjadi apabila Laju Filtrasi
Glomeruler (LFG) kurang dari 60 ml/menit/1,73m2 selama tiga bulan atau lebih.
Berbagai faktor yang mempengaruhi kecepatan kerusakan serta penurunan fungsi
ginjal dapat berasal dari genetik, perilaku, lingkungan maupun proses degeneratif
(Gabriyelin, 2016). PGK didefinisikan sebagai kelainan struktur atau fungsi ginjal
11
lebih dari 3 bulan dengan implikasi terhadap kesehatan. (McManus dan Wynter-
Minott, 2017).
2.2.2 Epidemiologi Penyakit Ginjal Kronik
Di Amerika Serikat menurut The United States Renal Data System
(USRDS) dengan menggunakan data dari National Health and Nutrition
Examination Survey (NHANES) memperkirakan bahwa prevalensi gagal ginjal
kronik di Amerika Serikat adalah 13,6% pada sekitar 44 juta penduduk. Penyakit
ginjal kronik lebih sering terjadi pada orang yang berusia lebih dari 60 tahun pada
orang Amerika dan Afrika (Schonder et al., 2016).
Di Indonesia kejadian penyakit ginjal kronik meningkat seiring
bertambahnya usia, berdasarkan hasil Riskedas tahun 2018 prevalensi PGK di
Indonesia meningkat dari 2% menjadi 3,8% dengan prevalensi pada laki-laki lebih
tinggi daripada perempuan yaitu (0,471%) lebih tinggi dari (0,352%) terjadi
peningkatan yang signifikan pada kelompok usia 45-54 tahun (0,56%), usia 55-64
tahun (0,72%), dan tertinggi pada kelompok usia 65-74 tahun (0,82%), sedangkan
pada usia ≥75 tahun (0,74%). Menurut Infodatin 2017, perawatan penyakit ginjal
merupakan ranking kedua pembiayaan terbesar dari BPJS kesehatan setelah
penyakit jantung. DKI Jakarta merupakan provinsi tertinggi yang pernah/sedang
cuci darah pada pendududuk berumur ≥15 tahun yang pernah didiagnosis penyakit
ginjal kronik dan jawa timur berada pada urutan ke 9 (RISKESDAS, 2018).
Gambar 2. 3 Prevalensi PGK di Indonesia (RISKESDAS, 2018)
12
2.2.3 Klasifikasi Penyakit Ginjal Kronik
Penyakit ginjal dapat diklasifikan menjadi 5 berdasarkan kondisi ginjal yaitu
stage 1 – 5, setiap stage memiliki karakteristik sendiri. Penentuan kondisi ginjal
dapat ditentukan dengan Glomerulus Filtration Rate (GFR). GFR digunakan
sebagai ukuran untuk mengetahui besarnya kerusakan ginjal karena filtrasi
glomerulus merupakan tahap awal dari fungsi nefron
Tabel II. 1 Klasifikasi CKD berdasarkan nilai GFR (KDOQI, 2014)
GFR
Category
GFR (mL/min/1.73
m2)
Terms
G1 ≥90 Normal or high
G2 60-89 Midly decreased
G3a 45-59 Midly to moderately
decreased
G3b 30-44 Midly to severely
decreased
G4 15-29 Severely decrease
G5 <15 Kidney failure
GFR dapat diperkirakan (eGFR) dengan studi Modification of Diet in Renal
Disease (MDRD). MDRD merupakan sebuah persamaan kreatinin serum. Usia
dan angka tersebut dapat bervariasi tergantung pada jenis kelamin dan etnis. GFR
dinyatakan dalam mL/min/1,732. eGFR dapat dihitung dengan rumus berikut :
eGFR (ml/menit/1,73 m2 ) = 186 x (Serum Kreatinin)-1,154 x (umur)-
0,203 x (0,742 jika perempuan) x (1,212 jika African American) (Pagana et
al., 2015).
The National Kidney Foundation merekomendasikan bahwa estimated GFR dapat
diperhitungkan sesuai dengan serum kreatinin, usia, berat badan dan jenis kelamin
(persamaan Cockcroft and Gault)
𝐺𝐹𝑅 𝑚𝐿/min =
13
2.2.4 Etiologi Penyakit Ginjal Kronik
Berdasarkan hasil Indonesia renal registry tahun 2018 untuk etiologi
penyakit ginjal kronik hipertensi kembali menjadi etiologi tertinggi yaitu 36% lalu
diikuti oleh nefropati diabetik yaitu 28% dan glomerupati primer 10%.
2.2.4.1 Hipertensi
Hipertensi adalah salah satu penyebab utama CKD karena efek buruk yang
meningkatkan TD pada pembuluh darah ginjal. Hipertensi tidak terkontrol
menyebabkan tekanan intraglomerular tinggi, mengganggu filtrasi glomerulus.
Kerusakan glomeruli menyebabkan peningkatan filtrasi protein, menghasilkan
peningkatan jumlah protein yang tidak normal dalam urin (mikroalbuminuria atau
proteinuria). Mikroalbuminuria adalah presentasi sejumlah kecil albumin dalam
urin dan seringkali merupakan tanda pertama CKD. Proteinuria (rasio protein
terhadap kreatinin ≥200 mg / g) berkembang ketika CKD berkembang, dan
dikaitkan dengan prognosis buruk untuk penyakit ginjal dan CVD. Hubungan
antara CKD dan HTN bersifat siklis, karena CKD dapat berkontribusi atau
menyebabkan HTN. Peningkatan TD menyebabkan kerusakan pembuluh darah di
dalam ginjal, serta di seluruh tubuh. Kerusakan ini merusak kemampuan ginjal
untuk menyaring cairan dan limbah dari darah, yang menyebabkan peningkatan
volume cairan dalam darah sehingga menyebabkan peningkatan TD (Buffet dan
Ricchetti, 2012).
2.2.4.2 Diabetes Melitus
Diabetes melitus merupakan penyebab tertinggi kedua pada penyakit ginjal
kronik atau juga sering dikenal dengan nefropati diabetik. Kerusakan pada
membrane glomerulus tidak hanya disebabkan oleh adanya penebalan membran
glomerulus teteapi juga akibat adanya peningkatana proliferasi sel-sel mesangial
dan peningkatan endapan bahan seluler dan non-seluler didalam matriks
glomerulus sehingga menyebabkan adanya akumulasi bahan padat pada sekitar
berkas kapiler. Saat kadar gula darah tidak terkontrol akan menyebabkan adanya
pengendapan protein glikosilasi dan pengendapan ini diyakini berkaitan dengan
kerusakan glomerulus sehingga struktur vascular di glomerulus mengalami
14
sclerosis (Strasinger, 2014). Berikut tabel dibawah tentang klasifikasi klinis
penyakit ginjal diabetik :
Tabel II. 2 Klasifikasi klinis penyakit ginjal diabetik (Strasinger, 2014)
Albuminuria Durasi Hipertensi Glomerulus filtration
rate
Fase 1
Hiperfiltrasi
< 30
mg/hari
Onset normal ↑ 20 -50 %
Fase 2
Normoalbuminuria
(Silent phase)
< 30
mg/hari
2-5 tahun normal Normal / ↑
Fase 3
Mikroalbuminuria
(Incipient)
30 – 300
mg/hari
5-15
tahun
tinggi Normal
Fase 4
Mikroalbuminuria
(over nephropathy)
>300
mg/hari
10-20
tahun
tinggi ↓ 12-15 ml/menit/tahun
Fase 5
PGTA
20-30
tahun
tinggi <10-15 ml/menit
2.2.4.3 Glomerulonefritis
Istilah glomerulonefritis merujuk pada proses inflamasi steril mengenai
glomerulus dan terkait temuan darah, protein dan silinder dalam urin. Terdapat
bermacam jenis glomerulonephritis dan kondisi dapat berkembang dari satu
bentuk kebentuk lainnya yaitu glomerulonephritis glomerulus progresif-cepat
menjadi glomerulofritis kronik yang dapat bekembang menjadi sindrom nefrotik
dan pada akhirnya penyakit ginjal kronik (Strasinger, 2014).
Glomerulonefritis akut adalah suatu penyakit yang ditandai dengan gejala
yang mendadak dengan gejala demam, edema di sekitar mata, hipertensi dan
hematuria. Glomerulonefritis progresif-cepat dengan prognosis yang lebih buruk
daripada glomerulonefrtis akut dan sering berakhir dengan penyakit ginjal. Gejala
dimulai dengan adanya pengendapan kompleks imun di dalam glomerulus.
Glomerulonefritis kronik dengan pemeriksaan menunjukkan adanya hematuria,
proteinuria, glukosuria sebagai akibat dari disfungsi tubulus dan beragam silinder.
Sindrom nefrotik ditandai dengan proteinuria masif yaitu lebih besar dari 3,5
15
g/hari, kadar albumin rendah, kadar lemak serum tinggi dan edema (Strasinger,
2014).
Gambar 2. 4 Etiologi Penyakit Ginjal kronik (IRR, 2018).
2.2.5 Patofisiologi Penyakit Ginjal Kronik
Saat nefron terluka dan sisa nefron akan hidup beradaptasi kompensasi,
dengan aliran darah per nefron dan terjadi hiperfiltrasi untuk menormalkan GFR
(hipotesis Brenner). Perubahan permeabilitas dinding kapiler glomerulus adalah
ciri dari penyakit glomerulus. Vasodilatasi ginjal merupakan gejala awal dan
menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan kapiler pada glomerulus dan cedera
pada dinding endotel intra glomerulus sehingga terjadi kerusakan glomerulus.
Proteinuria mungkin disebabkan oleh lesi glomerulus yang mendasari atau hasil
dari peningkatan tekanan intra-glomerular. Protein atau faktor yang terikat dengan
albumin yang rusak (seperti asam lemak, growt factor, atau produk akhir
metabolisme) mungkin menuju cedera sel tubulus proksimal, Sintesis sitokin lokal
(meningkatkan rekrutmen inflatori interstitial sel) lalu terjadi hipertrofi
glomerulus. Terjadi peningkatan produksi ECM menyebabkan glomerulosklerosis
sehingga terjadi chronic kidney disease (Steddon, 2014).
16
Gambar 2. 5 Patofisiologi PGK (Steddon, 2014).
2.2.6 Faktor Resiko Penyakit Ginjal Kronik
PGK disebabkan oleh 3 jenis faktor diantaranya adalah faktor kerentanan,
faktor inisiasi dan faktor progresi. Faktor kerentanan adalah faktor yang dapat
meningkatkan resiko penyakit ginjal namun tidak menyebabkan kerusakan ginjal
secara langsung, diantaranya adalah usia lanjut, berkurangnya massa ginjal, berat
lahir yang rendah, ras atau etnis minoritas, riwayat keluarga, pendapatan dan
pendidikan yang rendah, peradangan sistemik dan dislipidemia. Faktor inisiasi
adalah faktor yang dapat menyebabkan kerusakan ginjal secara langsung dan
dapat dimodifikasi dengan terapi obat, diantaranya adalah diabetes melitus,
hipertensi, glomerulonefritis, penyakit ginjal polikistik dan HIV nefropati.
Sedangkan faktor progresi adalah faktor yang mempercepat penurunan fungsi
ginjal setelah inisiasi dari kerusakan ginjal seperti glikemia pada penderita
diabetes, hipertensi, proteinuria, hiperlipidemia dan merokok (Hill et al, 2016).
17
2.2.7 Manifestasi Penyakit Ginjal Kronik
Pada PGK stage awal keadaan GFR masih normal kemudian fungsi nefron akan
menurun secara perlahan ditandai dengan adanya peningkatan kadar ureum dan serum
kreatinin. Ketika GFR 60-89% masih asimtomatik namun terjadi peningkatan kadar
ureum dan serum kreatinin. Ketika GFR sebesar 15-29% pasien mulai menunjukkan
gejala anemia, peningkatan TD, gangguan fosfor dan kalsium, pruiritus dan muntah.
Ketidakseimbangan elektrolit dan air juga terjadi.Selain itu pasien juga mudah
terkena infeksi seperti ISK. Pada saat LFG pasien PGK <15% maka pasien akan
menunjukkan gejala serta komplikasi yang lebih serius dan pasien memerlukan terapi
pengganti ginjal (kidney replacement) antara lain dialisis atau transplantasi ginjal.
Pada keadaan ini pasien sudah dikatakan masuk pada kategori Penyakit Ginjal Kronik
Stadium 5 (ESRD) (Hudson, 2014)
2.2.8 Komplikasi Penyakit Ginjal Kronik
2.2.8.1 Anemia
Menurut KDIGO (2012), anemia adalah kondisi kadar hemoglobin (Hb)
pasien <13 g/dL untuk laki-laki dewasa dan <12 g/dL untuk perempuan dewasa.
Eritropoietin diproduksi di ginjal oleh fibroblas interstitial peritubular kortikal.
Produksi eritropoietin oleh ginjal akan menurun apabila terjadi penurunan massa
ginjal yang berfungsi. Kekurangan zat besi juga merupakan faktor umum yang
berkontribusi terhadap anemia pada PGK. Metabolisme besi biasanya diatur
dengan ketat oleh hepcidin. Kelainan pada hepcidin dapat mengurangi
ketersediaan zat besi untuk erythropoiesis yang disebabkan oleh peradangan.
Erythrocytosis adalah kejadian yang jauh lebih jarang pada pasien dengan PGK.
Fungsi trombosit yang rusak dengan kecenderungan perdarahan diketahui terjadi
pada pasien dengan PGK lanjut dan uremia (Berns, 2015).
2.2.8.2 Ketidakseimbangan Na+ dan Air
Ginjal berfungsi dalam menjaga keseimbangan natrium dan air. 130-147
mEq/L merupakan kadar Na+ normal didalam tubuh. Pada pasie PGK fungsi
ginjal terganggu menyebabkan terjadinya ketidak seimbangan elektrolit. Biasanya
pasien PGK mengalami kelebihan Na+ dan air. Apabi;a kelebihan Na+ berjalan
18
terus-menerus maka dapat menyebabkan terjadinya gagal jantung, hipertensi dan
edema perifer. Kelebihan air menyebabkan hiponatremia (Perlman et al., 2014).
2.2.8.3 Hiperkalemi
Penurunan eksresi kalium pada pasien PGK sangat berbahaya karena
mengakibatkan hiperkalemi. Hiperkalemia dapat diklasifikasikan menjadi 3
menurut kalium serum yaitu : ringan (5,5-6,5 mmol / l), sedang (6,5-7,5 mmol / l)
dan hiperkalemia berat (> 7,5 mmol / l). Hiperkalemia berpotensi mengancam
jiwa kondisi di mana serum kalium melebihi 5,5 mmol / l. Pada pasien gangguan
fungsi ginjal, terutama ketika GFR <15 ml / menit, apabila terjadi sedikit
peningkatan asupan potasium dapat menyebabkan hiperkalemia berat. Selain
gagal ginjal akut dan kronis, hipoaldosteronisme, dan kerusakan jaringan masif
seperti pada rhabdomyolysis merupakan kondisi khas yang menyebabkan
hiperkalemia. Gejala tidak spesifik dan sebagian besar terkait dengan disfungsi
otot atau jantung (Lehnhardt dan Kemper, 2011).
2.2.8.4 Mineral Bone Disorder (Renal Osteodystrophy)
Gangguan tulang dan mineral termasuk defisiensi hidroksivitamin D, umum
terjadi pada semua pasien PGK. Gangguan tersebut bertambah parah oleh
hiperfosfatemia yang diakibatkan oleh berkurangnya eksresi fosfat sehingga
mengurangi konsetrasi kalsium serum terionisasi dan menyebabkan menurunnya
jumlah kalsium dalam tulang dan dalam jaringan lunak. Hipokalsemia dan
hiperfosfatemia menghasilkan peningkatan sekresi hormon PTH. Ginjal tidak
dapat menanggapi PTH dengan meningkatkan reabsorpsi kalsium ginjal. Kadar
PTH tetap meningkat dan terjadi hiperplasia kelenar paratiroid.
Hiperparatiroidisme sekunder menghasilkan gangguang pada struktur tulang
normal dan ini disebut osteosclerosis (pergeseran tulang) (Whittlesea, 2019).
2.2.8.5 Uremia
Uremia yaitu ketika terjadi penumpukan hasil dari efek biologis dan
metabolit yang tidak diekresikan sehingga tertahan di dalam tubuh. Metabolit
tersebut kemudia disebut dengan retens uraemik atau racun uraemik jika
memberikan efek toksik (Vanholder et al., 2016).
19
2.2.8.6 Asidosis Metabolik
Asidosis metabolik terjadi akibat hilangnya kemampuan ginjal dalam
menjalankan fungsinya dalam mengekskresikan asam dan menghasilkan basa.
Terjadi penurunan GFR secara progresif sehingga terjadi penurunan pH <7,35
dan ketika plasma [HCO3] < 22 mEq /yang menandai awal asidosis metabolik
(Goraya dan Wesson, 2017). Asidosis menyebabkan pH dalam darah dan jaringan
rendah atau berada dibawah pH normal karena tingginya konsentrasi ion H+. Pada
kondisi normal nilai pH untuk tubuh manusia yaitu 7,40 ± 0,02 untuk tekanan
parsial CO2 (pCO2) adalah 38 ± 2 mmHg dan untuk konsentrasi HCO3 yaitu 24 ± 2
mmol/L. Sekitar 20 % pasien dewasa dengan PGK lanjut mengalami asidosis
metabolik (Harambat et al., 2017). Rendahnya konsentrasi bikarbonat membawa
beberapa konsekuensi negatif pada pasien, seperti peningkatan risiko
perkembangan penyakit ginjal, degradasi tulang yang lebih tinggi oleh osteoklas,
dan penghambatan osteoblast, peningkatan kematian, peradangan, dan kekurangan
gizi (Rodrigues Neto Angéloco et al., 2018).
2.2.9 Data Laboratorium
Untuk memastikan adanya penyakit ginjal kronik maka perlu dilakukan uji
laboratorium. Berikut parameter uji laboratorium yang dapat digunakan untuk
menentukan adanya penyakit ginjal kronik :
1. Urinalisis : Memberikan informasi awal tentang gangguan penyakit ginjal
kronik dengan kerusakan metabolisme (Strasinger, 2014).
Warna : Kuning pucat - kuning
Kejernihan : jernih tidak terlihat partikulat, transparan
Berat Jenis : 1,015 - 1,030
pH : 4,5 – 8,0
2. Klirens Kreatinin : penilaian fungsi ginjal berdasarkan laju filtrasi
glomerulus masih banyak yang menggunakan kreatinin karena biaya yang
lebih murah, mudah dilakukan dan klirens kreatinin adalah parameter yang
baik untuk menilai fungsi ginjal (Rahmawati, 2018). Pada pasien penyakit
ginjal kronik akan mengalami penurunan pada nilai klirens kreatininnya.
Nilai normal pada orang dewasa (<40 tahun) yaitu :
20
Pria : 107-139 mL/menit
Wanita : 87-107 mL/menit
Egfr : >60/mL/menit/1,73 m2 (Pagana et al., 2015).
3. BUN (Blood Urea Nitrogen) : BUN biasanya digunakan dalam kombinasi
dengan kreatinin serum konsentrasi sebagai tes skrining sederhana untuk
mendeteksi kelainan fungsi ginjal. Pasien penyakit ginjal kronik
mengalami peningkatan pada nilai BUN. Nilai BUN normal pada orang
dewasa : 10-20 mg/dL (Pagana et al., 2015).
4. Serum Kreatinin : kadar kreatinin di plasma relatif konstan dan
klirensnya dapat diukur sebagai indikator laju filtrasi glomerulus. Metode
analisis yang digunakan untuk mengukur kreatinin adalah metode kimia
berdasarkan reaksi Jaffe, metode enzimatik dan High performance liquid
chromatography (HPLC). Nilai kreatinin serum normal: 0,6 – 1,3 mg/dL.
Kreatinin serum > 1,5 mg/dL menunjukkan telah adanya gangguan fungsi
ginjal (Rahmawati, 2018).
5. Serum dan Urinary Cystatin C Cystatin C adalah 132 sistein protease
inhibitor asam amino (13,3 kDa) diproduksi oleh semua sel tubuh berinti
yang dianggap biomarker fungsi ginjal. Konsentrasi cystatin mulai
meningkat ketika GFR turun di bawah 88 mL/mnt/1,73 m2 (0,85mL/s/m
2). Konsentrsi cystain yang disarankan pada anak yang lebih tua dari usia
1 tahun 0,70-1,38 mg/L dan 0,55 hingga 1,37 mg/ L pada orang dewasa
(Dipiro, 2011).
6. Anion Gap Kesenjangan anion, menunjukkan perbedaan dalam kation
dan anion yang tidak diukur, juga harus dihitung. Perbedaan anion yang
tinggi (>17 mEq/L [>17 mmol/L]) adalah sering hadir pada pasien
penyakit ginjal kornik dengan stadium 4 atau 5 karena akumulasi anion
organik, fosfat. Berikut perhitungan serum anion gap :
SAG = [Na+] − [Cl−] − [HCO3)
Anon gap normal adalah sekitar 9 mEq/L (9 mmol/L) dengan kisaran 3
hingga 11 mEq/L (3–11 mmol/L) (Dipiro, 2015).
Menurut Rahmawati, 2018 berikut nilai normal ion yang digunanakan
dalam perhitungan anion gap:
21
Kalium (K+
) : 3,5 – 5 meq/L.
Natrium (Na+) : 136 – 146 meq/L.
Klorida (Cl-) : 95 – 107 mmol/L
Fosfat : 2,5 – 4,5 mg/dl.
Bikarbonat : 20 – 28 mmol/L (Patrick, 2014).
2.2.10 Penatalaksanaan Penyakit Ginjal Kronik
2.2.10.1 Terapi Konservatif
Terapi yang dapat diberikan dengan non-farmakologis yaitu dengan
membatasi (diet) asupan protein hingga 0,8g/kg/hari jika GFR <30
mL/menit/1,73m2, berhenti merokok untuk memperlambat perkembangan
penyakit dan mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Selain itu terapi non-
farmakologis lainnya yaitu melakukan olahraga minimal 30 menit lima kali dalam
seminggu untuk mencapai body massa index (BMI) 20 hingga 25 kg/m2 (Dipiro,
2015).
2.2.10.2 Terapi Terhadap Komplikasi
Tujuan dari terapi pada pasien penyakit ginjal kronik yaitu untuk menunda
perkembangan CKD, meminimalkan perkembangan atau keparahan komplikasi.
terdapat dua terapi yaitu terapi farmakologis dan terapi non-farmakologis, untuk
terpai farmakologis disesuaikan berdasarkan manifestasi yang terjadi pada pasien.
Penatalaksaan secara farmakalogis berdasarkan manifestasi yang dialami
yaitu sebagai berikut :
2.2.10.2.1 Hipertensi
Secara umum, untuk pasien dengan Penyakit Ginjal Kronik (PGK), ACE
inhibitor dan ARB dianggap sebagai agen antihipertensi lini pertama oleh
sebagian besar pedoman, terutama pada kondisi albuminuria (ekskresi albumin>
300 mg / d). Terapi lini kedua agen antihipertensi pada pasien dengan PGK yaitu
diuretik karena pilihan yang masuk akal bagi sebagian besar pasien dengan PGK
terutama dalam mengatur terjadinya peningkatan volume urin dan diuretik akan
22
menurukan GFR. Diuretik seperti tiazid adalah antihipertensi yang efektif dengan
kemungkinan melalui mekanisme vasodilatory tidak langsung (Ku et al., 2019).
2.2.10.2.2 Anemia
Definisi anemia menurut KDIGO adalah apabila kadar Hemoglobin (Hb)
kurang dari 13 g/dL (130 g/L; 8,07) mmol/L) untuk pria dewasa dan kurang dari
12 g/dL (120 g/L; 7,45 mmol/L) untuk perempuan dewasa (Dipiro, 2015).
Anemia pada pasien PGK memberikan hasil yang buruk dan menurunkan
kualitas hidup. Pemberian zat besi, dan erythropoietin rekombinan dan turunan
sintetiknya (epoetin alfa, epoetin beta, darbepoetin alfa, metoksi polietilen
glikolepoetin beta; secara kolektif dikenal sebagai erythropoietic-stimulating
agent [ESA]) banyak digunakan untuk mengobati anemia dan telah terbukti
mengurangi kebutuhan transfusi darah pada orang dengan PGK (Webster et al.,
2017).
2.2.10.2.3 Hiperkalemia
Pada pasien PGK jumlah nefron berkurang sehingga ekskresi kalium
tidak berjalan normal dan terdapat penumpukan kalium yang menyebabkan
hiperkalemi. Pasien hiperkalemi harus dilakukan monitoring terhadap perubahan
EKG Kebanyakan terapi medis untuk hiperkalemia hanya menyediakan perbaikan
sementara dengan mengubah K+ menjadi intraseluler ruang tanpa benar-benar
menghilangkan kalium. Pemberian dekstrosa dan infus insulin memberikan efek
yang segera terlihat tetapi diperlukan pemantauan efek samping hipoglikemi. Ca-
gluconas juga dapat diberikan pada pasien hiperkalemi. Terapi selanjutnya juga
dapat diberikan untuk meningkatkan eksresi kalium dengan pemberian diuretic
seperti furosemide (Lehnhardt, 2010).
2.2.10.2.4 Hiperfosfatemia
Penatalaksanaan hiperfosfatemia pada pasien PGK difokuskan pada
pengendalian faktor-faktor yang bertanggung jawab untuk asupan dan
pembuangan fosfat dari tubuh. Ada 3 strategi utama untuk memperbaiki
hiperfosfatemia yaitu membatasi asupan fosfat dari makanan, meningkatkan
eliminasi dengan menghilangkan fosfat dengan dialisis yang memadai,
meminimalkan penyerapan fosfat dengan mengurangi penyerapan diusus dengan
menggunakan agen pengikat fosfat (Calcium-based phosphate binders (calcium
23
carbonate and calcium acetate, non-absorbable Polymers (sevelamer), heavy
Metal Salts (lanthanum carbonate and aluminium hydroxide) (Shaman dan
Kowalski, 2016). Agen pengikat fosfat merupakan pengobatan lini pertama untuk
mengontrol kadar serum fosfor dan kalsium (Dipiro, 2015).
2.2.10.2.5 Asidosis Metabolik
Asidosis metabolik terjadi akibat penurunan konsentrasi bikarbonat dalam
plasma sehingga terjadi penurunan pH darah (asidosis tidak terkompensasi)
(Blanco, 2017). Penatalaksanaan utama pada penderita gangguan keseimbangan
asam basa untuk menstabilkan kondisi dan diikuti dengan memperbaiki penyebab
yang mendasari. Terapi tambahan diberikan tergantung pada keparahan dari
gejala. Penanganan secara farmakologi pada keadaan asidosis metabolik dapat
diberikan natrium sitrat, kalium sitrat, kalium bikarbonat, dan natrium bikarbonat.
Penanganan secara farmakologi pada keadaan alkalosis yaitu dengan Bertujuan
pengobatan untuk memperbaiki faktor yang bertanggung jawab untuk
mempertahankan alkalosis dan tergantung pada apakah kelainan tersebut responsif
atau resisten terhadap natrium klorida (Dipiro, 2015).
2.2.10.3 Terapi Pengganti Ginjal
Pada pasien penyakit ginjal dengan stadium akhir terdapat 3 pilihan
perawatan utama yaitu hemodialysis (HD), Dialisis peritoneal (PD), dan
transplantasi ginjal (Dipiro, 2011). Pasien penyakit ginjal stage 4 dengan nilai
LFG 15-30 mL/menit/1,73 m2 dan stage 5 yang memiliki nilai LFG <15
mL/menit/1,73 m2 perlu adanya terapi pengganti untuk mengganti fungsi
ginjalnya (Ziegler et al., 2014).
2.2.10.2.1 Hemodialisis
Hemodialisis (HD) sangat penting sebagai upaya untuk mencegah
komplikasi, mengatur keseimbangan ureum, memperpanjang usia harapan hidup
dan meningkatkan kualitas hidup bagi pasien penyakit ginjal kronik. Hemodialisis
menggantikan fungsi ginjal manusia yaitu membersihkan darah dengan cara
membuang produk-produk sisa metabolism yang berbahaya, membuang ekses
cairan dan menyeimbangkan elektrolit. Biasanya hemodialisis dilakukan tiga kali
dalam seminggu (Syamsudin, 2011). Darah dikeluarkan dari pasien, antikoagulan,
24
dipompa melalui dialyser dan kemudian kembali ke pasien. Di dalam alat tersebut
darah dan dialisat (mengalir ke arah yang berlawanan) dipisahkan oleh membran
dialisis semi-permeabel (Steddon et al., 2014).
2.2.10.2.2 Dialisis Peritoneal
Dialisis peritoneal hampir sama dengan hemodialisis yaitu terapi dengan
menggantikan fungsi ginjal. Cateter ditanamkan ke dalam rongga peritoneum.
Pertukaran ini dapat dilakukan baik secara manual (dialisis peritoneal rawat jalan
terus menerus (CAPD)) atau menggunakan mesin (dialisis peritoneal otomatis
(APD)). Selama pertukaran dialisis zat terlarut kecil (Urea, kalium, kreatinin)
berdifusi dari sirkulasi ke dialisat dan dihilangkan saat efluen dikeringkan.
Dengan CAPD standar pendekatannya adalah dengan melakukan empat
pertukaran selama periode 24 jam menggunakan 2 liter dialisat pada setiap
kesempatan. Resep dapat bervariasi sesuai dengan kebutuhan setiap individu.
Dengan APD, mesin dialisis melakukan pertukaran berulang semalam dan pasien
memiliki pertukaran siang hari tambahan. Air dihilangkan melalui osmotik efek
glukosa dalam dialisat, meskipun agen osmotik lainnya dapat juga digunakan,
termasuk icodextrin, suatu polimer glukosa, dan asam amino. Komplikasi yang
paling umum adalah peritonitis (Gillis dan Wilkie, 2019).
2.2.10.2.3 Transplantasi Ginjal
Transplantasi ginjal adalah terapi pengganti ginjal dengan menanamkan
ginjal dari pendonor kepada penderita penyakit ginjal kronik. Namun kebutuhan
transplantasi ginjal jauh melebihi jumlah ketersediaan ginjal yang ada dan
biasanya ginjal yang cocok dengan pasien adalah yang memiliki kaitan keluarga
dengan pasien. Sehingga hal ini membatasi transplantasi ginjal sebagai
pengobatan yang dipilih oleh pasien. Transplantasi ginjal ini juga dapat
menimbulkan komplikasi akibat pembedahan atau reaksi penolakan tubuh (Nisa,
2015).
2.3 Tinjauan Tentang Asidosis metabolik pada penyakit Ginjal Kronik
2.3.1 Definisi Asidosis Metabolik
Asidosis metabolik terjadi jika pH sistemik turun <7,35 dan kadar HCO3
turun. Hal tersebut terjadi melalui kehilangan bikarbonat (usus atau ginjal), retensi
25
asam, Produksi atau pemberian asam berlebihan (HCl) (Steddon, 2014). Asidosis
metabolik adalah rendahnya konsentrasi serum bikarbonat dalam tubuh yaitu <22
mmol/L, sekitar 20 % pasien dewasa dengan PGK lanjut mengalami asidosis
metabolik (Harambat et al., 2017). Penanganan ginjal terhadap H+ selama terjadi
asidosis dan alkalosis tergantung pada efek langsung dari status asam-basa plasma
pada ginjal sel tubular. Dalam keadaan normal, tubular proksimal dan sel
interkalasi tipe A sebagian besar aktif, mempromosikan sekresi H+ bersih dan
reabsorpsi HCO3- (Sherwood, 2016). Untuk derajat asidosis ditentukan
berdasarkan kadar pH yaitu pH 7,2-7,29 asidosis ringan sedangkan pH<7,2
asidosis berat (Itzel, et all, 2008).
2.3.2 Epidemiologi Asidosis metabolik pada PGK
Diperkirakan bahwa asidosis metabolik hadir pada pasien PGK 2,3%
hingga 13% individu di PGK Tahap 3 dan 19% hingga 37% individu di Tahap 4
(Rodrigues Neto Angeloco et al, 2017). Kebanyakan pasien yang tidak tergantung
dialisis tidak memiliki asidosis metabolik karena kompensasi produksi NH3 ginjal
dan penyangga tulang. Namun, 15% pasien dengan CKD memiliki asidosis
metabolik, dan prevalensi meningkat pada setiap stagenya. Misalnya, dalam
peserta, Chronic Renal Insufficiency Cohort (CRIC) prevalensi asidosis metabolik
adalah 7% pada tahap 2, 13% pada tahap 3, dan 37% pada tahap 4 penyakit ginjal
kronik (Raphael, 2019).
2.3.3 Etiologi Asidosis Metabolik
a. Penyakit Ginjal, ginjal tidak dapat mengeksresikan atau terjadi
penurunan fungsi ginjal dalam mengeksresikan asam sehingga terjadi
penumpukan H+ (Sherwood, 2016).
b. Diare Berat, selama diare HCO3- akan hilang dari tubuh dan HCO3
- yang
tersedia untuk buffer H+ berkurang sehingga menyebabkan lebih banyak
H+
(Sherwood, 2016).
c. Diabetes Melitus, adanya metabolisme lemak abnormal akibat
ketidakmampuan untuk menggunakan glikolis karena jumlah insulin
yang tidak memadai menyebabakn pembentukan asam keto berlebih dan
meningkatkan plasma H+
(Sherwood, 2016).
26
d. Olahraga Berat, pada saat olahraga berat otot menggunakan glikolisis
anaerob terjadi produksi asam laktat dan peningkatan plasma H+
(Sherwood, 2016).
2.3.4 Patofisiologi Asidosis Metabolik pada PGK
Gambar 2. 6 Patofisologi Asidosis Metabolik pada PGK (Kraut, 2012)
Pada individu dengan fungsi ginjal normal akan menghasilkan hidrogen
yang cukup untuk mendapatkan kembali semua bikarbonat yang difilter dan akan
disekresi sekitar 1 mEq/kg Ion hidrogen perhari yang didapatkan dari
metabolisme protein makanan, maka akan dipertahankan pH cairan tubuh normal
melalui dapar hidrogen oleh ion protein, hemoglobin, fosfat dan bikarbonat.
Sedangkan pada pasien gagal ginjal kronis parah (stage IV dan V) semua
bikarbonat tersaring tetapi terjadi penurunan kemampuan ginjal untuk mensistensi
ammonia atau kemampuan ginjal terganggu. Penurunan dapar urin ini
menyebabkan jumlah ekresi asam dan keseimbangan ion hidrogen terus menurus
sehingga terjadi asidosis metabolik. Metabolisme yang signifikan secara klinis
asidosis umumnya terlihat ketika GFR turun di bawah 20 hingga 30 mL / mnt
pada stadium 4 PGK (Dipiro, 2015).
Ekskresi asam awalnya dipertahamkan
oleh peningkatan ekskresi ammonium
(NH4+)
Jumlah nefron yag berfungsi
pada pasien CKD menurun
Terjadi penurunan ekskresi
ammonium perGFR total tiga kali
diatas normal
Ketika GFR dibawah 40-50
mL/menit
Retensi ion hidrogen Penurunan pH
27
2.3.5 Gambaran Klinis Asidosis Metabolik pada PGK
Efek sistemik dari asidosis metabolik yang parah (pH <7,1) yaitu Air
Hunger (pernapasan Kussmaul, peningkatan volume tidal, dengan respirasi dalam
dan desah) dan hiperventilasi (untuk menghilangkan CO2) menurunkan
kontraktilitas miokard (menurunkan pelepasan Ca2+ dari sarkoplasma retikulum),
arteriodilatasi, dan venokonstriksi, Menggeser kurva disosiasi oksigen ke kanan
(lebih banyak melepaskan O2) dan Aritmia resisten (Steddon, 2014).
2.3.6 Penatalaksanaan Asidosis Metabolik pada PGK
Penatalaksaan pada asidosis metabolik adalah untuk mengatasi gangguan
yang mendasari. Pasien yang asimtomatik yaitu asidemia ringan sampai sedang
(HCO3- 12-20 mEq/L {12-20 mmol/L}; pH 7,2-7,4) dapat diberikan natrium
bikarbonat per oral. Pengobatan dilakukan secara bertahap satu hari sampai
beberapa minggu (Dipiro, 2015). Karena ginjal adalah rute utama untuk
mengeluarkan ion H+, CKD dapat menyebabkan asidosis metabolik. Ini akan
menyebabkan pengurangan dalam serum bikarbonat yang dapat segera diobati
dengan dosis oral natrium bikarbonat 1-6 g/hari. Karena takaran bikarbonat tidak
kritis, mudah untuk bereksperimen dengan dosis berbeda bentuk dan kekuatan
yang sesuai dengan pasien individu. Jika asidosis parah dan persisten, maka
dialisis mungkin diperlukan (Whittlesea, 2019).
2.4 Tinjauan tentang Buffer
Buffer adalah sistem penyangga asam basa kimiawi dalam cairan tubuh,
yang dengan segera bergabung dengan asam atau basa untuk mencegah perubahan
konsentrasi ion hidrogen yang berlebihan. Buffer ini bekerja dengan menetral kan
kelebihan ion hidrogen, bersifat temporer dan tidak melakukan eliminasi. Fungsi
utama sistem buffer adalah mencegah perubahan pH yang disebabkan oleh
pengaruh asam fixed dan asam organic pada cairan ekstraseluler (Seifter, 2014).
Buffer didalam tubuh dibagi menjadi 2 yaitu buffer ekstraseluler dan buffer
intraseluler. Fraksi penyangga yang dilakukan di luar kompartemen ekstraseluler
terjadi di dalam otot. Buffer intraseluler protein dan fosfat berfungsi sebagai
sistem penyangga. Di ruang intravascular protein darah khususnya Hb memiliki
28
kapasitas buffer. Pada buffer ekstraseluler asam bikarbonat/karbonat merupakan
sistem buffer yang paling penting diproduksi oleh aktivitas seluler. Larut dalam
cairan tubuh dan dihidrasi dalam suatu reaksi yang dikatalisis oleh anhidrase
karbonat untuk menghasilkan asam karbonat, yang dengan cepat terionisasi
menjadi bikarbonat dan H+. Konsentrasi HCO3
− tergantung pada jumlah CO2 yang
terlarut dan PCO2 (Blanco, 2017).
2.5 Tinjauan tentang Bikarbonat
2.5.1 Pembentukan Bikarbonat
Bikarbonat dihasilkan oleh ginjal melalui tiga proses yaitu : sekresi H+ dan
titrasi HPO4 yang disaring, metabolisme α-ketoglutarate yang berasal dari
glutamin dan metabolisme organik tersaring dan terserap kembali seperti laktat
dan sitrat (Kraut dan Nagami, 2018).
Pada sel tubular terjadi pembentukan H HPO42-
yang telah melalui
glomerulus akan bereaksi dengan hasil eksresi sel tubular yaitu H+ di lumen
tubular menjadi HPO4- yang akan dieksresi melalui urin. Namun Sekresi dan
ekskresi ion hidrogen ditambah dengan penambahan plasma HCO3. H+ yang
disekresikan tidak bergabung dengan HPO4 dan kemudian tidak diekskresikan.
Ekskresi H+ ditambah dengan adanya HCO3 baru dalam plasma. Pada pasien
asidosis ekskresi H+ terganggu sehingga terjadi penumpukan asam dan tidak
terjadi pembentuka HCO3 yang baru (Gambar 2.7) . (Sherwood, 2016).t
Gambar 2. 7 Pembentukan Bikarbonat (Sherwood, 2016)
Bikarbonat yang telah di filtrasi oleh glomerulus akan direabsorpi oleh
tubulus proksimal yang diperantai oleh penukar ion Na+/H+ (NHE3) yang terletak
pada membran luminal sel epitel. Lalu bikarbonat (HCO3-) akan bereaksi dengan
29
ion H+ menjadi H2CO3. H2CO3 tersebut berdisosiasi menjadi H2O dan CO2.
CO2 mudah menembus membrane lalu masuk kedalam sel tubulus dan berikatan
dengan H2O menjadi H2CO3. Setelah itu H2CO3 tersebut akan berdisosiasi
menjadi H+ dan HCO3-. HCO3- kembali ke cairan interstisial ginjal dan ke aliran
darah kapiler diikuti dengan pertukaran Na+ untuk mengganti proton H+ dari
dalam sel sehingga dapat mempertahankan konsentrasi Na+ intraseluler rendah.
Pada pasien penyakit ginjal kronik dengan asidosis metabolik terjadi penurunan
fungsi ginjal. Akibatnya tidak dapat memfiltrasi bikarbonat dengan baik sehingga
pembentukan bikarbonat menurun, kadar bikarbonat dalam darah menurun
menyebabkan pH menurun dan terjadilah asidosis metabolik (Katzung, 2015).
Gambar 2. 8 Mekanisme Fisiologis Bikarbonat (Katzung, 2015)
2.5.2 Sistem Bikarbonat
H2CO3 dan HCO3 adalah pasangan buffer yang paling penting sistem di
ECF untuk buffering perubahan pH dibawa oleh penyebab selain fluktuasi H2CO3
yang dihasilkan CO2. Ini adalah sistem penyangga ECF yang efektif karena dua
alasan. Pertama, H2CO3 dan HCO3 berlimpah di ECF, jadi sistem ini sudah
tersedia untuk menahan perubahan pH. Kedua setiap komponen pasangan
penyangga ini sangat erat diatur. Ginjal mengatur HCO32, dan pernapasan sistem
mengatur CO2, yang menghasilkan H2CO3.
30
Jadi, dalam tubuh H2CO3: HCO3 2 sistem penyangga termasuk keterlibatan
CO2 melalui reaksi berikut :
Gambar 2. 9 Sistem Bikarbonat (Sherwood, 2016)
Sistem penyangga bikarbonat terdiri dari larutan air yang mengandung dua
bahan: (1) asam lemah, H2CO3, dan (2) garam bikarbonat, seperti natrium
bikarbonat (NaHCO3). H2CO3 terbentuk dalam tubuh oleh reaksi CO2 dengan
H2O. H2CO3 yang terbentuk tanpa enzim karbonat anhydrase (berlimpah dalam
didinding alveoli paru-paru dan juga di dalam sel epitel tubulus ginjal) reaksinya
lambat dengan jumlah yang sedikit. Buffer bikarbonat adalah buffer ekstraseluler
paling kuat dalam tubuh disebabkan oleh dua elemen dari system buffer HCO3-
dan CO2 karena diatur oleh ginjal dan paru-paru. pH cairan ekstraseluler dapat
dikontrol dengan pengurangan atau penambahan HCO3- oleh ginjal dan tingkat
pengurangan kadar CO2 oleh paru-paru (Hall et al., 2016).
2.6 Tinjauan tentang Natrium Bikarbonat
Gambar 2. 10 Struktur Kimia Natrium Bikarbonat (PubChem, 2019)
Natrium Bikarbonat merupakan Agen alkali yaitu meningkatkan konsentrasi
bikarbonat plasma dan urin. 12 mEq bikarbonat setara dengan 1 g natrium
bikarbonat. Natrium Bikarbonat merupakan alkalinisasi yang paling sering
digunakan untuk terapi IV asidosis sistemik dengan rentang terapinya yaitu 24-31
mEq/L (Papich, 2016).
31
Gambar 2. 11 Mekanisme Sodium Bikarbonate (Papadakis, 2015)
Saat diberikan NaHCO3, NaHCO3 akan terpecah menjadi Na+ dan HCO3
-
lalu HCO3- dalam cairan ekstraselular akan bergabung dengan H
+ menjadi H2CO3.
H2CO3 terpecah menjadi H2O dan CO2 (diekskresikan melalui urin) sehingga pH
meningkat (Schrier, 2010)
Tabel II. 3 Tinjauan Natrium Bikarbonat (Ashley dan Dunleavy, 2019).
SODIUM BIKARBONAT
Rumus Molekul NaHCO3
BM 84
Indikasi - Asidosis Metabolik
- Asidosis tubulus ginjal
- Resusitasi berkepanjangan
Golongan Obat Elektrolit, agen alkalinisasi
Nama Dagang Meylon 8,4 % Injeksi, Sodium Bikarbonat 500 mg
tablet
Rute Oral dan Intravena
Dosis P.O : 0,5-1,5 g 3 kali sehari. Dosis umum: 1−2 mmol /
kg
Untuk menghitung dosis yang diperlukan berdasarkan
defisit basa (Berikan setengah dari dosis yang dihitung).
Encerkan hingga konsentrasi maksimum tidak lebih dari
0,5 mmol / mL (osmolaritas = 1000 mOsm / L).
IV: Infus selama minimal 30 menit
Monitoring Pantau keseimbangan asam-basa.
Pantau situs infus lokal untuk tanda-tanda ekstravasasi.
Kontraindikasi Asidosis respiratorik dan alkalosis
32
SODIUM BIKARBONAT
Interaksi Obat Penggunaan ketoconazole secara bersamaan dapat
mengurangi paparan ketoconazole.
Hindari pemberian natrium bikarbonat dan katekolamin
secara bersamaan (dopamin, dobutamin, adrenalin
(epinefrin), noradrenalin (norepinefrin)) melalui IV
yang sama kateter atau tabung, larutan natrium
bikarbonat akan menonaktifkan katekolamin.
Onset of action P.O : 15 menit IV : cepat setelah pemberian IV
Duration of action P.O : 8-10 menit IV : 1 – 2 jam
Ekskresi Melalaui urin < 1%
Efek Samping Hipernatraemia, Hiperosmolalitas, hipokalsemia,
hipokalemia. Jika diberikan selama ventilasi yang tidak
adekuat, PaCO2 dapat meningkat sehingga
memperburukm asidosis.
Nekrosis jaringan local trombosis di lokasi pemberian
Alkalosis dan tetani metabolik. Kram perut, mual,
muntah.
Penyimpanan Simpan botol di bawah 30 ° C. Larutan encer dapat
disimpan hingga 24 jam pada 2-8 ° C.
Asidosis metabolik sedang: 50 hingga 150 mEq natrium bikarbonat yang
dilarutkan dalam 1 L D5W untuk diinfus secara intravena pada kecepatan 1
hingga 1,5 L / jam selama jam pertama.
Asidosis metabolik yang parah: 90 hingga 180 mEq natrium bikarbonat
yang dilarutkan dalam 1 L D5W untuk diinfus secara intravena pada kecepatan 1
hingga 1,5 L / jam selama jam pertama. Jika status asam-basa tidak tersedia, dosis
harus dihitung sebagai berikut: 2 hingga 5 mEq / kg infus IV selama 4 hingga 8
jam; dosis berikutnya harus didasarkan pada status asam-basa pasien (Medscape,
2019).
Untuk menentukan dosis natrium bikarbonat iv perlu menghitung dengan
analisis pH dan gas darah dengan rumus :
Awalnya, berikan 25% -50% dari hasil perhitungan dalam cairan IV selama
20-30 menit. Natrium Bikarbonat terbagi atas dua kekuatan yaitu yang diberikan
secara perlahan dengan kekuatan 8,4% atau dengan intravena kontinu dengan
33
kekuatan lebih kecil yaitu 1,26%. Jumlahnya sesuai dengan besarnya kekurangan
basa (BPOM RI, 2015).
Contoh :
Pasien : Ny. X dengan umur 64 tahun dan berat badan 50 kg di diagnosa penyakit
ginjal kronik dengan asidosis metabolik. berdasarkan hasil analisa gas darah kadar
bikarbonat pasien yaitu 18 mEq/L dan pH 7,1.
N 𝐻
= 90
(Kebutuhan Bikarbonat)
Karena valensi NaHCO3 sama dengan 1 maka, 90 mEq/L = 90 mmol/L (1 ml = 1
mEq). Dosis diberikan ½ dari perhitungan = 45 mEq/L. 12 mEq bikarbonat setara
dengan 1 g natrium bikarbonat. Maka 15 mEq = 3,78 gram.
8,4% =
𝑚 maka,
𝑚
𝑚𝐿
𝑚
𝑚𝐿
x= 45 ml
Tabel II. 4 Sediaan Natrium Bikarbonat yang beredar di Indonesia (BPOM,
2017)
Natrium Bikarbonat
1. Nama Produk
Bentuk Sediaan
Komposisi
Kemasan
Pendaftar
Sodium Bicarbonate
Tablet 500 mg
Sodium Bicarbonate
-Botol Plastik @100 Tablet
BALATIF - Indonesia
2. Nama Produk
Bentuk Sediaan
Kemasan
Pendaftar
Diproduksi oleh
MEYLON 84-BP
Cairan Injeksi 8.4 %Sodium Bicarbonate
Dus, 120 Ampul Plastik @25 ml
OTSUKA Indonesia – Indonesia
OTSUKA Indonesia - Indonesia