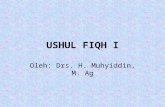USHUL FIQIH BARU - USHUL FIQH SEBAGAI DISCOURSE
-
Upload
mazizaacrizal-nisaa -
Category
Spiritual
-
view
2.599 -
download
10
description
Transcript of USHUL FIQIH BARU - USHUL FIQH SEBAGAI DISCOURSE

Brought By: Mazizaacrizal
a.k.a
Dewa ng’Asmoro Mudhun Bumi
Visit me at : www.mazizaacrizal.blogspot.com
: www.facebook.com/mazizaacrizal
E-mail : [email protected]
1

USHUL FIQIH BARU :
USHUL FIQH SEBAGAI “DISCOURSE”
ABSTRAK
Paradigma tekstualistik di sini adalah sebuah bentuk kerja pembacaan terhadap realitas yang ditundukkan pada optik tekstual. Hal ini mengonsekwensikan Ushul Fiqh yang berfungsi sebagai pengatur sistem nalar (al- Musyarri’ li al- Aql) melakukan konsentrasi penelitiannya hanya pada proposisi-proposisi teks dan bukan proposisi-proposisi realitas empiris. Hasil yang disuguhkan pun pada akhirnya terkesan mengawang-awang di langit daripada membumi.
Hakikat teks yang tidak bisa dilepaskan dari lingkup sosial budaya yang membentuknya, menyebabkan orientasi tekstual dalam menyelesaikan problem yang lahir dalam lingkup sosial dan budaya berbeda menuntut untuk dipertanyakan. Paradigma tekstual hanya cocok diaplikasikan dalam momentum yang disebut Yahya Muhammad sebagai “fase teks”. Sedangkan momentum lain yang sudah melampaui fase teks ini mengandaikan dilejitkannya paradigma pendekatan yang lain. Hal ini dikarenakan hakikat teks dan maknanya yang bersifat temporal dan partikularistik. Teks al-Quran dan Hadits yang pada kenyataannya merespon kondisi sosial dan budaya Arab abad ke 6 H sudah barang tentu tidak relevan untuk digunakan secara ‘asal comot’ dalam rangka merespon kondisi sosial dan budaya abad ke 21.
Paradigma Tekstualistik vis a vis KontekstualistikPerkembangan dunia dalam berbagai aspeknya memunculkan problem kemanusiaan
yang tidak hanya baru akan tetapi juga semakin kompleks. Problematika kemanusiaan itu sama sekali baru karena ia tidak pernah terjadi bahkan tidak pernah terpikirkan pada masa-masa sebelumnya. Ia juga semakin kompleks karena hampir tidak ada satupun masalah yang bisa diselesaikan dengan satu pendekatan dan sudut pandang. Pendekatan Ushul Fiqh yang diharapkan mampu merespon perkembangan ini ternyata harus menerima kenyataan pahit. Ushul Fiqh dengan paradigma klasiknya dinilai hanya mampu mewakili sudut pandang normatif-doktrinal yang tidak mampu menyelesaikan berbagai problem kontemporer. Paradigmanya yang tekstualistik menyebabkan sudut pandang doktrinal-normatif-teosentris lebih dominan daripada sudut padang sosiologis-historis-antroposentris.
Paradigma tekstualistik yang dimaksud di sini adalah sebuah bentuk kerja pembacaan terhadap realitas yang ditundukkan pada optik tekstual. Hal ini berkonsekuensi pada ushul fiqh yang berfungsi sebagai pengatur sistem nalar (al- musyarri’ li al-‘aql) melakukan konsentrasi penelitian hanya pada proposisi-proposisi teks dan bukan proposisi-proposisi
2

realitas empiris. Hasil yang disuguhkan pun pada akhirnya terkesan lebih mengawang-awang di langit daripada membumi.
Hakikat teks yang tidak bisa dilepaskan dari lingkup ruang dan waktu yang membentuknya, menyebabkan orientasi tekstual dalam menyelesaikan problem yang lahir dalam ruang dan waktu berbeda menuntut untuk dipertanyakan. Paradigma tekstual hanya cocok diaplikasikan dalam momentum yang disebut Yahya Muhammad sebagai “fase teks”. (Yahya,1999: 21-22) Sedangkan momentum lain yang sudah melampui fase teks ini mengandaikan dilejitkannya paradigma yang lain. Hal ini dikarenakan hakikat teks dan maknanya yang bersifat temporal dan partikularistik. Teks al-Quran dan Hadits yang pada kenyataannya merespon kondisi sosial dan budaya Arab abad ke 6 H sudah barang tentu tidak relevan untuk digunakan secara ‘asal comot’, dalam rangka merespon kondisi sosial dan budaya abad ke 21.
Atas dasar itulah ada kebutuhan yang mendesak untuk merumuskan paradigma ushul fiqh baru yang mampu mengakomodasi tidak hanya paradigma tekstualistik tetapi juga kontekstualistik. Inisiatif ini pada akhirnya akan mengantarkan kepada paradigma kontekstualistik ushul fiqh dengan pendekatan sosiologis-historis-antroposentris daripada doktrinal-normatif-teosentris yang memenjarakan umat Islam dalam kubangan sejarah masa lampau.
Adapun strategi pergeseran yang penulis tawarkan, di samping mengubah pendekatan doktrinal-normatif-teosentris ke arah sosiologis-historis-antroposentris yang memanfaatkan perkembangan keilmuan baru di luar dirinya, juga dibarengi dengan menjumput elemen-elemen progresif pada ushul fiqh klasik dan memaknainya kembali untuk konteks abad 21. Di sini terjadi proses membuang dan melestarikan. Kedua strategi ini bertolak dari pandangan bahwa elemen-elemen ushul fiqh semenjak awal perumusannya adalah entitas diskursus yang terus bergumul dan bukan sebagai entitas paradigmatis yang final.
Struktur Ushul Fiqh Klasik Menelaah struktur ushul fiqh klasik menemukan sebuah kenyataan bahwa ia dibangun
semata-mata mengarus kepada paradigma tekstualistik. Karena segala kasus yang hendak direspon dengan kerangka ushul fiqh harus dikembalikan kesimpulan hukumnya kepada teks-teks al-Quran dan Hadits. Hal ini berangkat dari asumsi kebanyakan cerdik pandai klasik bahwa segala permasalahan hidup sudah dibahas di dalam al-Quran dan Hadits, hal ini sekali lagi wajar, dalam lingkup sosio-kultur yang belum begitu berjarak dari masa kenabian.
Maka tidak heran apabila pembahasan yang ada di dalam ushul fiqh klasik terkonsentrasi pada upaya bagaimana mengungkap makna teks (bayân). Bayân didefinisikan pertama kali oleh Syafi’i sebagai pengajaran al-Quran yang turun dengan bahasa Arab sesuai dengan sistem pengungkapan maknanya. Tujuannya adalah mendefiniskan hubungan antara struktur bahasa dengan makna. Menurut Syafi’i, hubungan ini akan menjadi kabur jika tidak dibarengi dengan penguasaan bahasa Arab yang mencukupi.
Selanjutnya Syafi’I, memberikan batasan dan definisi sistem pemaknaan al-Quran. Pertama, pengajaran yang sifatnya nash, tak membutuhkan takwil atau penjelasan apapun karena memang sudah sedemikian jelas dengan sendirinya. Kedua, pengajaran yang sifatnya nash, akan tetapi masih membutuhkan penjelaskan dan penyempurnaan. Peran
3

penjelas dan penyempurna ini dilakukan oleh Hadits-hadits Nabi. Ketiga, pengujaran yang menjelaskan suatu kewajiban, akan tetapi tata cara dan detailitasnya dijelaskan kemudian oleh Hadits-hadits Nabi. Keempat, tidak ada pengujaran al-Quran akan tetapi Nabi menjelaskannya. Tingkat kekuatan argumentasinya sebanding dengan pengujaran al-Quran. Kelima, tidak ada pengujaran al-Quran dan Hadits sehingga mengharuskan umatnya untuk melakukan pencarian dengan ijtihâd. Jalan ijtihâd adalah dengan penguasaan bahasa Arab dan qiyâs. (Al-Jabiri,2002:103)
Jika kita mau mengkaji satu persatu sistem bayân yang dikontruksi Imam Syafi’i, maka kita menemukan ada item polemis yang sudah terjadi semenjak awal Islam, terutama dipicu paradigma ushul fiqh Abu Hanifah dan Imam Malik yang menjadi counter paradigma-nya. Item polemis itu terletak pada point yang bersangkut-paut dengan Hadits dan qiyâs. Mengenai penguasaan bahasa Arab, tidak ada polemik antara ulama Islam waktu itu. Saya kira ini adalah hal wajar, sebagaimana fenomena bahasa di manapun tidak mungkin dipahami kecuali dengan pengusaan bahasa yang bersangkutan.
Bahasa Arab mempunyai tata aturan bahasa tersendiri yang harus dikuasai jika hendak memahaminya, seperti nahwu, sharf dan ‘ilm al-lughah. Bahasa Inggris demikian juga mempunyai grammar, konjugasi dan leksikografi. Setiap bahasa memiliki tata aturannya sendiri, setiap bahasa mempunyai grammar masing-masing. Dalam arti, nahwu, sharf dan ‘ilm al-lughah adalah ilmu yang sifatnya partikular, karena terbatas hanya berkenaan dengan bahasa Arab.
Dalam hal ini, yang universal adalah ilmu Linguistik (al-Lisâniyyah) karena tujuannya adalah hendak merumuskan teori umum bahasa, pola-pola yang bekerja di dalamnya dan obyek kajiannya tidak hanya satu bahasa akan tetapi berbagai bahasa. Begitu juga ilmu baru Hermeneutika adalah universal karena obyek kerjanya adalah mengusut asumsi-asumsi yang berkerja di balik bahasa atau teks dan itu berlaku universal, tidak hanya ada dalam bahasa Inggris akan tetapi bahasa Arab, Perancis, Jerman dan lain sebagainya. Hemat penulis, Ilmu Lingusitik Hermeneutika akan sama-sama memberikan sumbangan positif bagi ushul fiqh.
Peran Hadits sebagai penjelas dan penyempurna al-Quran sebenarnya juga tidak ada yang mempertanyakan. Letak polemiknya lebih kepada tingkat selektifitas. Abu Hanifah ekstra selektif di dalam menggunakan Hadits, berbeda dengan Syafi’i yang terlihat lebih royal. Di lain sisi, Imam Malik mengakui tidak hanya Hadits, tetapi juga praktek penduduk Madinah (‘Amal Ahl al-Madînah) sebagai sumber hukum yang otoritatif.
Penolakan Abu Hanifah terhadap Hadits seputar pembagian harta rampasan perang (ghanimah) yang membedakan bagian bagi penunggang kuda, begitu juga penafsirannya yang rasional seputar khiyâr majlis ketika dihadapkan pada hadits “Al-bai’âni bi al-khiyâr hatta yaftariqâ”, menunjukkan selektifitas dan sekaligus rasionalitas Abu Hanifah dalam berijtihad.
Sedangkan qiyâs juga menjadi sumber polemik semenjak awal sejarah ushul fiqh. Abu Hanifa dan Imam Malik tentu menggunakan qiyâs, akan tetapi keduanya menyadari keterbatasannya sehingga yang pertama menawarkan Istihsân, sedangkan yang kedua melegitimasi ‘Amal Ahl Al Madinah dan Mashalih Mursalah. Ibn Hazm yang datang belakangan mengkritik keras qiyâs yang justru menurutnya terlalu keluar dari hukum-hukum yang diterapkan al-Quran dan Hadits. Begitu juga Ahmad Ibn Hanbal yang menyanggah penggunaan qiyâs sebagai metode ijtihad.
4

Pada akhirnya wacana yang menyangkut elemen-elemen ushul fiqh pada awal teoritisinya berakhir dengan diterimanya paradigma Syafi’I, bahkan oleh para pakar non Syafi’iyyah seperti Malikiyyah, Hanafiyyah, Hanabilah bahkan Syi’ah. Bisa dikatakan paradigma ushul fiqh mereka berada di dalam kerangka teoritik hasil kontruksi Syafi’i. Struktur ushul fiqh semua madzhab kemudian mengacu kepada struktur yang dibangun Syafi’i kecuali pada momen-momen kreatif sebagai manifestasi pergeseran paradigmatis seperti dalam Qawa’idul Ahkam fi Mashalih Al Anam (Izzudin Ibn Abdissalam), al- Burhan (al-Juwayni), al-Mustashfa (al-Ghazali) dan al-Muwafaqat (al-Syatibi). Meskipun kesemunya masih berada dalam satu paradigma tekstualistik yang juga mengakui Hadits sebagai penjelas dan qiyas sebagai mekanisme ijtihad.
Paradigma Syafi’i diterima oleh semua kalangan karena hemat penulis ia rasional pada masanya. Kerangka sistemnya merupakan pertautan logis yang tidak bisa dibantah oleh pakar sekaliber al-Juwayni, al-Ghazali dan al-Syatibi dari kalangan madzhab yang berbeda. Tanpa merendahkan peran mereka dalam melakukan modifikasi yang realtif, mereka hanya bisa mengikuti kerangka dasarnya. Kesepakatan ini tidak hanya terjadi pada sistem bayân dalam lima item yang telah saya sebutkan, akan tetapi juga pada sistem bayân lainnya yang membahas ‘am-khas, nasikh-mansukh dan lainnya.
Begitulah, paradigma ushul fiqh Syafi’i saya kira cukup rasional untuk konteks yang terbatas, yaitu fase teks. Polemik Hadits tidak mampu meruntuhkan peran dan posisi Hadits sebagai penjelas dan penyempurna. Karena ia bersifat logis dalam mekanisme pemaknaan al-Quran dengan memahami kedudukan Allah dan Nabi Muhammad sebagaimana dijelaskan oleh Syafi’i. Begitu juga polemik qiyâs adalah perdebatan wajar dalam konteks fase teks, di mana kubu yang menyerangnya justru hendak munundukkan segala kasus kepada al-Quran dan Hadits. Pertarungan antara kubu qiyâs dan anti qiyâs adalah lebih kepada pertarungan antara fuqaha sebagai kaum rasional di satu sisi dengan muhadditsîn sebagai kaum doktrinal yang banyak mengoleksi Hadits dan mutakallimîn yang memandang syariah sebagai taken for granted (ta’abbud) di lain sisi. ( Mahmud Abdul Majid, 1399: 89) Syarkh, Khasyiah dan Khulashah; Antara Mengembang dan Mengempis
Islam semenjak abad ke 4 H menyaksikan berakhirnya potensi kreatifitas. Jargon ditutupnya pintu ijtihad menggantikan keharusan berijtihad sebagaimana masa-masa awal. (Wael B,1983) Masa ini ditandai dengan tingkat kreativitas dan orisinalitas intelektual yang lebih rendah. Karya yang dihasilkan merupakan komentar (syarkh) terhadap karya-karya tokoh hukum seperti Imam Malik, al-Syaibany dan al-Syafi`i. Lalu dari komentar itu dikomentari lagi (khasyiah) dengan sudut pandang yang saling mengintervensi.
Setelah komentar atas komentar diikuti dengan resume (ikhtisahar) dengan ciri-ciri tulisan yang ketat.( N.Coulson, 1964:84) Dengan begitu, teks berada di antara perluasan dan penyempitan, pengembangan dan pengempisan, penyakupan dan pengerdilan. Jika tujuan dari komentar adalah supaya teks itu hidup di atas dirinya sendiri dan menjadi semacam “channel” untuk mengumpulkan informasi-informasi linguisitik dan dasar-dasar yang lain, maka tujuan dari resume adalah memfokuskan dan menjaga inti dari teks. Memegangnya erat-erat.
Dalam konteks kepengarangan ushul fiqh, Syarkh, khasyiah dan khulashah dimulai pada abad ke 7 H. Teks asli terakhir adalah al-Ahkam Fi Ushula Al- Ahkam (Al Amidi)
5

(631 H). Setelah itu, ketika budaya intelektual ushul fiqh mengalami degradasi etos kreatifitas, dimulailah komentar-komentar dan resume. Meski sampai abad ke 13 masih tersisa momen kreatif al-Syaukaniy (1255 H) dalam Irsyad Al Fukhul. ( Syihabuddin Ibn Al Abbas Ahmad Ibn Idris Al Qarafi,684 H) lihat juga (Al-Razi,606 H) Akan tetapi tetap tidak menjadi mainstream.
Kontruksi kepenulisan syarkh, khasiyah, khulashah, tadyil (catatan atas statemen) dan taqrirat ( Afirmasi atas statemen) keluar dari struktur teks asli. Keluar bukan berarti menyimpang. Ia hanya bergerak dari dalam teks pada level ungkapan, bisa jadi mengomentari, menjelaskan atau memberikan tambahan dari disiplin ilmu lain. Ia merupakan obyek kajian tersendiri. Bagaimana sebuah pemikiran berdiri di tempat dan mengelilingi dirinya sendiri, tertutup di wilayah edar teks. Berputar dan menggelembung tanpa sedikitpun keluar seperti keluarnya seekor ulat dari kepompongnya.
Karya-karya ini justru seharusnya menjadi obyek kajian. Tentang sebuah kreatifitas yang mundur dan bukan kreatifitas yang maju. Ketika pemikiran itu hidup dalam dirinya sendiri dan mengingat-ingat masa lalunya. Memanggil kembali ingatan masa silam tanpa akal berpikir sampai di mana dirinya. Mengerjakan sesuatu yang lampau dan bukan kekinian atau masa depan. Ibarat onta padang pasir ketika tidak menemukan apa yang harus dimakan, ia suka memakan kembali apa yang telah ia muntahkan.
Ketika budaya hidup di atas dirinya, ia menggelembung dari dalam. Ibarat balon yang semakin besar dengan udara. Ia tak membesar kecuali dari dalam. Di dalam resume terjadi penciutan ke dalam. Yaitu ketika udara berkurang bertahap sampai ketika menyentuh kulit balon itu sendiri. Teks pertama. Kerangkanya yang dasar. Di dalam dua fenomena itu tidak ada penambahan baru dan kreatifitas struktur. Keduanya bergerak di tempat, lambat ketika melakukan komentar dan cepat ketika melakukan resume.
Praktis dalam kesadaran seperti ini yang terjadi adalah materi-materi ushul fiqh terulang. Terjadi redundansi berkali-kali. Kontruksi keilmuan dan paradigma pemikiran karya-karya itu sama belaka. Setiap karangan yang datang dibangun di atas masa lalu, menambah detil-detilnya, mengganti strukur ungkapan atau mengubah arah bahasanya. Materi-materi yang terulang dan serupa lebih banyak daripada materi yang berbeda-beda. Berada di dalam sebuah budaya yang tidak mengenal hak paten pemikiran, pengutipan terjadi tanpa mencantum referensi. Pemikiran sangat kolektif, strukturnya tetap dan ilmunya sangat membudaya. ( Hanafi, 2004: 31)
Tradisi ini dalam beberapa aspek memang elaboratif. Kreatifitas relatif bisa diketemukan seperti dalama al-Mahshul karya al-Razi yang sebetulnya merupakan kombinasi antara al-Burhan karya al-Juwaini dan al-Mustashfa karya al-Ghazali. Beberapa buku lain juga cukup membantu memudahkan pembacaan terhadap teks asli dan menyediakan beberapa detailitas. Tentu harus ada apresiasi relatif terhadap karya-karya ini. Akan tetapi perkembangan dunia tidak mengizinkan tradisi ini diteruskan tanpa memperhatikan ilmu pengetahuan yang berkembang di luar dirinya kemudian memasukkannya menjadi bagian dari struktur organik ushul fiqh.
Ushul Fiqh Sebagai Sebuah “Discourse”Ushul fiqh pada awalnya adalah sebuah wacana. Hal itu seperti tergambar dalam
narasi perdebatan konseptor ushul fiqh klasik dalam masalah Hadits, qiyâs, ijm’a, Istihsan, Amal Ahl al-Madinah dan Mashalih Mursalah. Menyangkal Hadits sebagai penjelas dan
6

penyempurna al-Quran adalah tidak logis karena pada kenyataannya banyak aspek al-Quran tidak bisa digali tanpa sinaran Hadits. Perdebatan paling jauh hanya sampai kepada selektifitas pemakaian Hadits.Pengingkaran terhadap qiyâs, harus diartikan sebagai kehati-hatian menjaga fiqh dari penalaran hitam-putih
dan lebih mengutamakan kembali kepada Hadits yang pada saat itu lebih aktual, fleksibel dan otentik. Sedangkan pemakaian qiyâs sebetulnya juga diniatkan sebagai upaya dinamisasi fiqh sehingga mampu menjangkau berbagai permasalahan yang berkembang. Penyeimbang qiyâs dari penilaian hitam putih ditawarkan oleh Abu Hanifah dengan metode Istihsan yang hendak keluar dari qiyâs Rajih menuju Qiyâs Marjuh. Pertimbangannya adalah keadilan dan kemaslahatan. ( Ahmad Amin: 156.)
Dan begitu juga Imam Malik lebih menggunakan Mashalih Mursalah atau ‘Amal Ahl Al Madinah daripada qiyâs.
Beberapa orientalis dan pemikir Islam seringkali mengembalikan dua metode ini pada pengedepanan “local custom” dan “customary law” yang menjadi ciri has fiqh Abu Hanifah dan Imam Malik. ( J. Scahcht, 1964:28) Meski bukan berarti Syafi’i sama sekali tidak mempunyai kepekaan terhadap keduanya. Dan Abu Hanifah tetap saja memakai qiyâs dalam batas-batas tertentu. Ia mengatakan “Laula al-atsar laqultu bi al-qiyas”.( Musthafa Tsalabi, 1986: 259) Pengedepanan Imam Malik kepada Atsar al-Shahabah dan Amal Ahl Madinah adalah lebih kepada dalam rangka menjaga validitas dan otentisitas dan bukan alasan “local custom” ataupun “customary law”.
Penolakan beberapa cerdik pandai klasik terhadap Mashalih Mursalah harus dimaknai sebagai kekhawatiran membuka peluang oknum tertentu dalam menafsirkan hukum Islam sesuai dengan kepentingan subyektif, dan tidak berdasar pada dalil al-Quran dan Hadits. Di samping itu juga dalam rangka meminimalisir tindakan spekulatif yang semata-mata didasarkan pada Mashalih Mursalah seperti kasus sebagian hakim yang menyarankan Umar Ibn Abdil Aziz untuk membunuh pihak yang melecehkan khalifah demi stabilitas negara. Khalifah waktu itu menolak karena hal itu tidak ada dalil yang mewajibkan membunuh oknum yang menghujat Khalifah.
Sedangkan Istihsan dioperasionalkan, ketika qiyâs dalam kasus tertentu tidak mampu mempertahankan tujuan hukum yaitu kemaslahatan. Seperti Abu Yusuf yang mewajibkan denda kepada perajin yang menerima pesanan (al-shana’) meski qiyâs justru mengatakan sebaliknya. Begitu juga Abu Hanifah yang mewajibkan bagian zakat kepada Bani Hasyim meski qiyâs melarangnya berdasarkan Hadits “Annahâ la tahillu liy muhammad wa la liy ahli muhammad”. Penolakan Syafi’i terhadap Istihsan ditujukan kepada oknum yang terlalu mudah menggunakan Istihsan sehingga melampaui tujuan hukum sebenarnya (kemaslahatan). Maka kritik Syafi’i lebih cocok ditujukan bukan pada konsep Istihsan itu sendiri, akan tetapi penyalahgunaan Istihsan dan operasionalisasinya yang terlalu mudah.
Ijma’ juga tidak kalah ramai menjadi wacana yang diperdebatkan. Dalam al- Risalah, konsepsi al-Syafi’i seputar Ijma’ disuguhkan dalam bentuk tanya jawab yang tidak disebut lawan paradigmatisnya. Di akhir bab “Qath al-‘Abdi” dalam al-Umm kita mendapatkan al-Syafi’i menolak konsep Ijma Imam Malik (Amal Ahl Al Madinah) kemudian persetujuannya terhadap Ijma’ Sharih tetapi bukan Ijma’ Sukuti. Dalam Ijma’ al-‘Ilm, al-Syafi’i menegaskan pendapatnya tentang kemungkinan terjadi Ijma’ pasca Shahabat. ( Abu Bakr Al Jashash,1993:39) Konsepsi yang ditolak kalangan Hanabilah terutama Ibn Taymiah yang hanya melegitimasi Ijma Shahabat. Bahkan Imam Ahmad Ibn Hambal
7

sendiri berbeda dengan al-Syafi’i karena dia lebih menyepakati ‘Amal Al-Ahl Madinah sebagaimana Imam Malik.
Ijma’ pada saat itu adalah konvensi para cerdik pandai yang dipilih masyarakat. Imam Syafi’i juga menguatkan premis itu. ( Abu Bakr Al Jashash, 1993:39) Dalam konteks modern adalah kesepakatan yang dicapai di parlemen-parlemen modern. Ijtihad individual berpotensi menuju Ijma’ jika bersepakat dengan ijtihad-ijtihad individual yang lain. Pada masa Tabi’in contoh ke arah Ijma’ adalah praktek Umar Ibn Abdil Aziz untuk membetuk sebuah parlemen yang duduk di sana beberapa pakar untuk menetapakan sebuah hukum.
Struktur Ushul Fiqh BaruPergeseran paradigmatis ushul fiqh akan mempengaruhi struktur ushul fiqh. Hassan
Hanafi telah menelusuri sejarah kepengarangan ushul fiqh semenjak al-Risâlah hingga Irsyad al-Fukhul Ilay Tahqiq Al haq fi ‘Ilma al-ushul. Dia menemukan adanya pergeseran paradigmatis, dan dengan begitu merubah bangunan struktur ushul fiqh. Pergeseran itu, menurut Hanafi terjadi diantaranya pada al-Mustashfa karya al-Ghazali dan al-Muwafaqat karya al-Syatibi ( Hanafi:24). Hanya saja hemat penulis, keduanya masih berada di bawah bayang-bayang al-Risalah di mana peran epistemologi bayân masih begitu kuat di mana metode induktif masih tunduk pada deduktif ayat-ayat al-Quran ( Nu’man Jughaim, 2002).
Orientasi inferensi makna pada ushul fiqh klasik secara keseluruhan jika dipaksa untuk diterapkan dalam konteks kekinian, maka yang terjadi adalah prioritas (aulawiyyah) teks (al-nash) daripada konteks (al-waqi’). Karena dalam paradigma klasik, al-Quran menunjukkan makna hukum hanya dengan melalui analisa makna, struktur bahasa, mafhum dan ma’qul-nya. Hasilnya adalah kesimpulan hukum yang doktrinal-normatif-teosentris.
Menelaah struktur ushul fiqh klasik, jika dilihat dari kerangka kekinian, yang terlihat adalah konstruk kesadaran teoritis yang menggelembung mengalahkan kesadaran praksis. Dalam Kesadaran teoritis ada wujud kental pengarusutamaan teks daripada realitas, huruf daripada makna dan kata daripada substansi. Akal berfungsi hanya sebatas pada pemetikan rasio legis dan seberapa jauh kehadirannya dalam premis mayor (ashl) dan premis minor (far’). Sehingga, tidak bisa tidak akal kehilangan kegeniusan dan daya tangkap yang langsung terhadap realitas dan lebih dekat dengan kemaslahatan. Hasil ijtihad melalui qiyâs, paling jauh akan menghasilkan kesimpulan makna yang masih dalam bayang-bayang teks yang temporal dan partikular itu.
Sedangkan dalam level kesadaran praksis, akan terselubung prioritas yang berlebihan terhadap Tuhan daripada manusia, 'kepentingan Tuhan' daripada kepentingan manusia, yang transenden daripada yang empiris. Mudah dinilai bahwa struktur organis terlemah ushul fiqh klasik jika hendak diterapkan dalam konteks sekarang adalah konsep 'makna' dalam kesadaran teoritis dan konsep 'tujuan' dalam level kesadaran praksisnya. Konsep ‘tujuan’ baru terlihat pada Izzudin Ibn Abdissalam dalam Qawâid al-Ahkam fî Mashalih al-Anam dan kemudian pada al-Syatibi dalam al-Muwafaqat. ( Al Syatibi, 2003)
Ushul fiqh baru harus berdiri di atas dua pilar paradigma tekstualistik yang doktrinal-normatif-teosentris dan kontekstualistik yang sosiologis-historis-antroposentris. Keduanya berjalan bersamaan. Yang pertama berdiri di atas perangkat bahasa Arab, nahwu, sharf dan ‘ilm al-lughah dan begitu juga ‘ilm al-lisaniyyah sebagaimana disyaratkan al-Syafi’i. Pada level ini perdebatan klasik mengenai elemen-elemen ushul fiqh bisa ditampilkan, begitu
8

juga produk-produk hukumnya. Akan tetapi ia harus ditundukkan pada konteksnya karena pada saat yang sama paradigma kontekstualistik yang berdiri di atas pendekatan sosiologis-historis-antroposentris dijalankan dalam rangka penundukan teks pada konteksnya dan sekaligus dalam rangka memproduksi makna baru sesuai dengan konteks kekinian dan kedisinian.
Hal itu dibarengi dengan pembacaan yang sama terhadap indikasi-indikasi progresif elemen ushul fiqh klasik seperti Istihsan dan Mashalih Mursalah. Ia ditarik ketengah setelah sekian lama menjadi wacana pinggiran dalam Ushul Fiqh klasik. Qiyâs pada saat ini dilakukan setelah selesai menilik pertimbangan empiris dengan pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang humanitis, sosial dan eksak untuk mempertajam pemahaman realitas luar. Posisi ilmu humanitis, sosial dan eksak dalam hal ini bukan dalam rangka menggantikan ushul fiqh akan tetapi sebagai perangkat baca terhadap realitas.
Begitu juga prosedur yang sama dilakukan ketika mengoperasionalkan elemen Istihsan dan Mashalih Mursalah dalam konteks modern. Mashalih Mursalah diperasionalkan ketika melalui telaah empiris kemaslahatan, yang diperjuangkan adalah kemaslahatan publik dan bukan kemaslahatan satu pihak, sebagaimana dikonsepsikan pengusung Mashalih Mursalah sendiri dalam konteks Ushul Fiqh klasik.(Tsa'labi:294). Ijma’ pada hakikatnya adalah pengalaman kolektif dan komunal yang bisa dilegitimasi dalam parlemen dalam konteks modern. Sedangkan ijtihad adalah pengalaman indvidual. (Hasaan Hanafi:22) Ia akan menjadi opini hukum yang sifatnya bisa diusulkan ke pemerintah dan bisa diterapkan jika disetujui.
Ibn Al Muqaffa menganggap ijtihad-ijtihad fuqaha sebagai bersifat usulan dan tidak harus diterapkan oleh pemerintah. Hanya lembaga pemerintah yang berhak untuk mempertimbangkan mana hasil ijtihad yang harus diterapkan di pengadilan-pengadilan (Al Jabiri, 2004:349. ).Dalam konteks modern pemerintah bisa mempertimbangkan apakah hasil ijtihad sesuai dengan konstitusi dan relevan untuk diterapkan atau tidak. Masyarakat bahkan para hakim tidak bisa mendirikan sebuah lembaga individu atau swasta untuk melakukan proses hukum selain yang dilakukan di bawah pemerintah. Kesemua elemen-elemen Ushul Fiqh pada hakikatnya terus bergumul dan terus menerus menjadi sebuah diskursus. Ia bisa diperdebatkan, ditambahi dan dikembangkan.
Pada permulaannya, hukum, etika dan norma memang sebuah kalam (wahyu), akan tetapi ia tidak mengawang dari realitas dan mengacuhkan karakterisitiknya yang berubah-rubah. Salah satu hal yang perlu dicatat adalah Al-Quran turun secara bertahap dalam situasi dan keadaan bangsa Arab abad ke 6 H yang spesifik. ( Yahya Muhammad, 2002:65) Ia kemudian dipahami dan diterjemahkan dengan bahasa manusia melalui perangkat bahasa dan empirisme demi kemaslahatan manusia dalam konteks yang berkembang. Dengan aplikasi metode induktif Al Syatibi, dan pakar-pakar sebelumnya seperti Al Juwaini, Al Ghazali, Izzudin Ibn Abdissalam dan Al Qarafi, wahyu akan menjadi penjamin beberapa prinsip fundamental seperti agama (al din), kehidupan (al nafs), keturunan (al nasl), akal (al a’ql), dan harta (al mal). ( Al Syatibi, II:8)
Pijakan konseptual proses humanisasi wahyu inilah yang kemudian dipraktekkan dan menjadi regulasi-regulasi, etika dan norma yang diberlakukan dengan konsekwensi hukum tertentu atau dalam bahasa agamanya disebut Wajib, Sunnah, Mubah, Makruh dan seterusnya (Al Ahkam). ( Al Syatibi, II:8)
9

PenutupLetak persoalan paling krusial kemandulan ushul fiqh bukan pada keniscayaan
distingsi konseptual antara al-Tsabit dan al-Mutahawwil (Adonis), al-Risalah dan al- Nubuwwah (Syahrur) dan Idea Moral dan Legal Spesifik (Fazlurrahman). Membicarakan elemen-elemen itu dalam tradisi Islam tidak akan mampu menggeser struktur ushul fiqh dari dalam. Akan tetapi yang harus dipecahkan, dan ini paling krusial, adalah krisis paradigma espitemologis ushul fiqh itu sendiri yang harus kembali dibangun di atas landasan dan tiang-tiang kontekstual. Bisa jadi krisis ini pertama kali selesai di tangan Syafi’i, dengan melakukan pembatasan peran nalar dan sekaligus membebaskan diri dari pendekatan yang terlalu literal.
Pada konteks saat ini, ketika paradigma al-Syafi’i dan Ushuliyyun klasik tidak lagi relevan menyelesaikan problem baru yang lebih kompleks, maka reformulasi paradigma ushul fiqh dengan mengombinasikan paradigma tekstualistik dan kontekstualistik bisa jadi menjadi solusi bagi kenyataan pahit yang dihadapi Ushul Fiqh abad ke 21 ini. Mengingat ushul fiqh sekarang ini tidak lagi hanya menjadi ‘musuh’ mereka yang berada di luar disiplin ini, akan tetapi juga ‘musuh’ bagi praktisi-praktisi yang sejak lama mempelajari ushul fiqh. Dengan begitu, ushul fiqh harus diyakini bukan lagi produk manusia yang kudus dan final akan tetapi sejatinya adalah sebuah “discourse” yang dinamis. Wallahu a’lam bi al- showab!
DAFTAR PUSTAKA
Abdulllah, Amin. Ushul Fiqh: Menuju Ijtihad Kontekstual (Jogjakarta: Fakultas Syariah Press, 2004).
Abdissalam, Izzuddin Ibn, Qawaid Al Ahkam fi Mashalih Al Anam (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah, 1999).
Amin, Ahmad, Dluha Al Islam, Vol. II (Beirut: Dar Al Kitab Al Arabi, Tanpa tahun Al Jabiri, Al Andalusi, Ibn Hazm, Al Muhalla, Vol. I-II, Beirut: Dar Al Afaq Al Jadidah, Tanpa tahun).
Al Jabiri, Muhammad Abid, Al ‘Aql Al Siyasi Al Arabi; Muhaddadatuhu wa Tajaliyyatuhu (Beirut: Markaz Dirasah Al Wahdah Al Arabiyyah, 2004).
10

-----------, Takwin Al A’ql Al Arabi (Beirut: Markaz Dirasat Al Wahdah Al Arabiyyah, 2002).
Al Jashash, Abu Bakr, Al Ijma’ dalam Zahir Syafiq Kabbi, Al Ijma; Diratsah fi Fikratihi min Khilal Tahqiq Bab Al Ijm, (Beirut: Dar Al Muntakhab Al Arabi, 1993).
Al Raysuni, Ahmad, Nadlariyyah Al Maqashid ‘Inda Al Imam Al Syatibi (Virgnia: Al Dar Al ‘Alamiyyah Li Al Kitab Al Islami, 1995).
Al Syafi’i, Muhammad Ibn Idris, Al Risalah, Muhammad Nabil Ghanaim (Ed.) dalam Taqrib Al Turats; Al Risalah (Cairo: Markaz Al Ahram Li Al Tarjamah wa Al Nasyr, 1988).
------------, Jima’ Al ‘Ilm (Beirut: Dar Al Kutub Al ‘Ilmiyyah, Tanpa tahun).Al Syatibi, Abu Ishaq, Al Muwafaqat fi Ushul Al Syari’ah (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah,
2003).Bek, Khudlari, Tarikh Al Tasyri Al Islami (Beirut: Dar Al Fikr, 1967).Coulson, Noel James, A History of Islamic Law (Chicago: Edinburgh University Press,
1964). Fyzee, Asaf A. A., Outlines Of Muhammadan Law (London: Oxford University Press,
1955.Hanafi, Hassan, Min Al Nash ila Al Waqi’; Takwin Al Nash, , Vol. I, Cairo: Markaz Al
Kitab Li Al Nasyr, 2004).-----------, Min Al Nash ila Al Waqi’; Bunyah Al Nash, Vol. II (Cairo: Markaz Al Kitab Li
Al Nasyr, 2004).Hallaq, Wael B., The Gate of Ijtihad: A Study in Islamic Legal History (Ann Arbor:
University Microfilms International, 1983).Izzuddin, Ibn Zughaiba, Al Maqashid Al ‘Ammah Li Al Syariah Al Islamiyyah (Cairo: Dar
Al Shafwa, 1996).Jughaim, Nu’man, Thuruq Al Kasyf ‘An Maqashid Al Syari’ (Amman: Dar Al Nafais,
2002).Karim, Khalil Abdul, Judzur Al Tarikhiyyah li Al Syari`ah Al Islamiyyah (Cairo: Siyna’ li
Al Nasyr, 1990).Majid, Abdul Hamid Mahmud Abdul, Al Ittijahat Al Fiqhiyyah ‘Inda Al Muhadditsin,
(cairo: Maktabah Al Khanji, 1399).Muhammad, Yahya, Madkhal Ila Fahmi Al- Islam (Beirut: Al Intisyar Al Arabi, 1999).-----------, Jadaliyyah Al Khitab wa Al Waqi’ (Beirut: Al Intisyar Al Arabi, 2002). Rahman, Fazlur, Membuka Pintu Ijtihad, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1995).Schacht, Joseph, An Introduction to Islamic Law (Oxford: Oxford university Press, 1964).Syahrur, Muhammad, Al Kitab wa Al Quran (Damaskus: Al Ahali Li Al Thaba'ah wa Al
Nasyr wa Al Tauzi', Tanpa tahun).Tsalabi, Musthafa, Ushul Al Fiqh Al Islami (Beirut: Dar Al Nahdlah Al Arabiyyah, 1986).Zahrah, Muhammad Abu, Ibn Hazm; Hayatuhu wa 'Ashruhu, Ara'uhu wa fiqhuhu, (Cairo:
Dar Al Fikr Al Arabi, 2004).-----------, Al Syafi'i; Hayatuhu wa 'Ashruhu, Ara'uhu wa Fiqhuhu (Cairo: Dar Al Fikr Al
Arabi, 1996).-----------, Ibn Taymiah; Hayatuhu wa 'Ashruhu, Ara'uhu wa Fiqhuhu (Cairo: Dar Al Fikr
Al Arabi, 2000).
11

12