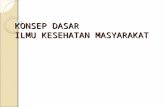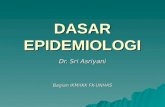tugas ikm
-
Upload
novita-elmy-mufida -
Category
Documents
-
view
10 -
download
0
description
Transcript of tugas ikm
-
5/20/2018 tugas ikm
1/7
1. Apakah perbedaan air bersih dan air minum?
Air Bersih
Beberapa pengertian air bersih menurut beberapa literature diantaranya adalah :
1. Air bersih adalah air sehat yang dipergunakan untuk kegiatan manusia dan harus bebas
dari kuman-kuman penyebab penyakit, bebas dari bahan-bahan kimia yang dapat
mencemari air bersih tersebut. Air merupakan zat yang mutlak bagi setiap mahluk hidup
dan kebersihan air adalah syarat utama bagi terjaminnya kesehatan (Dwijosaputro, 1981).
2. Menurut Peraturan Menteri Kesehata RI Nomor : 41 6/Menkes/Per/IX/1990 tentang
syarat-syarat pengawasan kualitas air, air bersih adalah air yang digunakan untuk
keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat
diminum apabila telah dimasak.
Air Minum
Berikut beberapa pengertian air minum menurut beberapa literature :
1. Menurut Permenkes RI No. 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang SyaratSyarat dan
Pengawasan Kualitas Air bersih, Air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi
syarat-syarat kesehatan dan langsung dapat diminum.
2. Menurut Permendagri No. 23 tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara
Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum, Departemen dalam
Negeri Republik Indonesia, Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau
tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
2. Apakah syarat air bersih?
Menurut Kusnaedi (2004), syarat-syarat kualitas air bersih, antara lain:
1. Syarat Fisik
Persyaratan fisik untuk air bersih, antara lain: airnya jernih tidak keruh, tidak berwarna, rasanya
tawar, tidak berbau, suhunya normal (20- 260C), tidak mengandung zat padatan.
-
5/20/2018 tugas ikm
2/7
2. Syarat Kimia
Kualitas air tergolong baik bila memenuhi persyaratan kimia, antara lain: pH netral, tidak
mengandung zat kimia beracun, tidak mengandung garam-garam atau ion-ion logam, kesadahan
rendah, tidak mengandung bahan kimia anorganik.
3. Syarat Biologis
Air tidak boleh mengandung Coliform. Air yang mengandung golongan Coli dianggap telah
terkontaminasi dengan kotoran manusia (Sutrisno, 2004). Berdasarkan PERMENKES RI No.
416/MENKES/PER/IX/1990, persyaratan bakteriologis air bersih adalah dilihat dari Coliform
tinja per 100 ml sampel air dengan kadar maksimum yang diperbolehkan adalah 50.
3. Apakah syarat jamban yang baik?
Menurut Depkes RI (2007), jamban yang memenuhi syarat adalah:
1. Kotoran tidak mencemari permukaan tanah, air tanah dan air permukaan
2. Cukup terang
3. Tidak menjadi sarang serangga (nyamuk, lalat, lipan, dan kecoa)
4. Selalu dibersihkan agar tidak menimbulkan bau yang tidak sedap
5. Cukup lobang angin
6. Tidak menimbulkan kecelakaan
4. Peraturan Perundangan terkait air bersih
Pada awalnya pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) banyak dilakukan olehpemerintah pusat. Tetapi sejalan dengan upaya desentralisasi melalui PP No.14 Tahun 1987
tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah,
urusan pembangunan, pemerliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana air minum
diserahkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Meskipun urusan tersebut telah diserahkan,namum pendanaannya masih dapat dibantu sebagian oleh Pemerintah pusat. Penyerahan urusan
pembangunan, pemerliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana air minum sebagai
wewenang dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota tersebut selanjutnya dipertegasdalam Pasal 16 Undang-Undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Pasal 40 PP
No.16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan rumusan
memenuhi kebutuhan air minum masyarakat di wilayahnya sesuai dengan standar pelayanan
minimal yang ditetapkan.
-
5/20/2018 tugas ikm
3/7
Penetapan wewenang dan tanggung jawab tersebut sejalan pula dengan pengaturan dalam
Pasal 14 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan
urusan penyediaan prasarana dan sarana umum serta pelayanan dasar bagi masyarakat diKabupaten/Kota sebagai urusan wajib Pemerintah Kabupaten/Kota. Tentunya lingkup atau
pengertian dan urusan penyediaan prasarana dan sarana umum serta pelayanan dasar bagi
masyarakat di Kabupaten/Kota tersebut mencakup pula penyediaan air minum bagi masyarakat.
Untuk mengatur pengembangan sistem penyediaan air minum nasional yang sekaligus
terintegrasi dengan pengelolaan air limbah dan persampahan, Pemerintah telah menetapkanpengaturannya dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah (PP) No.16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sisitem Penyediaan Air Minum (SPAM). Pasal 23 Peraturan Pemerintah tersebut
juga menegaskan bahwa perlindungan air baku dilakukan melalui keterpaduan pengaturan
pengembangan SPAM dan prasarana dan sarana sanitasi, yang meliputi sarana dan prasarana airlimbah dan persampahan. Hal mendasar lainnya yang diatur dalam PP tersebut adalah bahwa
Pemerintah bertanggung jawab dan wajib untuk menjamin penyelenggaraan pelayanan air
minum yang berkualitas, melalui :
- Terciptanya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga
terjangkau,- Terciptanya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa
pelayanan,
- Meningkatnya efisiensi dan cakupan pelayanan air minum dan sanitasi.
Hingga kini, penyediaan air bersih masih menjadi persoalan serius negeri ini. Dan jika
dikaitkan dengan salah satu target Millenium Development Goals (MDGs) dimana pada tahun
2015 setidaknya separo (50%) masyarakat dunia sudah harus mendapatkan akses terhadap airbersih, maka Indonesia mungkin menjadi salah satu negara yang harus menata diri untuk
mencapai target global tersebut.
Air sehat bagi seluruh rakyat, seyogyanya didefinisikan sebagai air minum. Ketentuan
tentang air minum, sebagaimana tertuang dalam PP No.16 / 2005 tentang Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum, adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atautanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
Persyaratan kesehatan air minum ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No.
907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat Syarat dan Pengawasan Air Minum.
Pemenuhan kebutuhan air minum tidak saja diorientasikan pada kualitas sebagaimana
persyaratan kesehatan air minum, tetapi sekaligus menyangkut kuantitas dan kontinuitasnya.
Pemerintah dan Pemerintahan di daerah berkewajiban menyelesaikan persoalan penyediaan airminum yang memenuhi ketentuan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas untuk seluruh rakyat,
khususnya terhadap masyarakat yang masih belum memiliki akses terhadap air minum. Di sisi
lain, Pemerintah mempertimbangkan pemenuhan akses masyarakat terhadap air minumberlandaskan tantangan nasional dan global.
Upaya melindungi sumber air baku, saat ini mendapatkan perhatian yang cukup serius
dari pemerintah. Hal ini berangkat dari kesadaran masyarakat dan pemerintah bahwa sumber air
-
5/20/2018 tugas ikm
4/7
sebagai unsur lingkungan yang vital merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat
menjamin berlanjutnya kehidupan.
Berbagai peraturan perundang-undangan dikeluarkan seperti yang dituangkan dalam
Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, UU No. 23/1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No.41/1999 tentang Kehutanan, UU No.7/2004 tentangSumber Daya Air. Peraturan-peraturan pelaksanaannya antara lain dituangkan dalam Peraturan
Pemerintah No.22/1982 tentang Tata Pengaturan Air, PP 27/1991 tentang Rawa, PP 35/1991
tentang Sungai, PP 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air,PP 16/2004 tentang Penatagunaan Tanah dan Keppres No. 32/1990 tentang Pengelolaan
Kawasan Lindung.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, apabila master plan dan sistem jaringan air bersih akan
disusun, landasan hukum yang dapat digunakan dalam penyusunan adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
2.
Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang3. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup
4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah5. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum
6. Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan BadanUsaha dalam Penyediaan Infrastruktur
7. Peraturan Pemerintah No. 22/1982 tentang Tata Pengaturan Air
8. Peraturan Pemerintah No. 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian
Pencemaran Air9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 294/PRT/M/2005 tentang Badan Pendukung
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum10.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan StrategiSistem Penyediaan Air Minum
11.Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat Syarat
dan Pengawasan Air Minum
5. Peraturan perundangan terkait pengelolaan sampah
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga- UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
Terdapat beberapa muatan pokok yang penting yang diamanatkan oleh peraturanpemerintah ini, yaitu:
1. Memberikan landasan yang lebih kuat bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan
pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dari berbagai aspek antara lain legal
-
5/20/2018 tugas ikm
5/7
formal, manajemen, teknis operasional, pembiayaan, kelembagaan, dan sumber daya
manusia;
2. Memberikan kejelasan perihal pembagian tugas dan peran seluruh parapihak terkaitdalam pengelolaan sampah mulai dari kementerian/lembaga di tingkat pusat, pemerintah
provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, pengelola kawasan sampai
masyarakat;3. Memberikan landasan operasional bagi implementasi 3R (reduce, reuse, recycle)dalam pengelolaan sampah menggantikan paradigma lama kumpul-angkut-buang;
4. Memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelibatan dunia usaha untuk turut
bertanggungjawab dalam pengelolaan sampah sesuai dengan perannya.
6. Peraturan perundangan terkait pengelolaan sampah
PP tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun seperti yang diamanatkan
dalam Pasal 58 ayat (2) UU 32/2009
PP tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun seperti yang
diamanatkan dalam Pasal 59 ayat (7) UU 32/2009
PP Dumping Limbah seperti yang diamanatkan dalam Pasal 60 ayat (3) UU32/2009.
7. Program kesehatan masyarakat terkait penyediaan air bersih
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) adalah salah satuprogram yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan dukungan Bank Dunia, programini dilaksanakan di wilayah perdesaan dan pinggiran kota.
Program Pamsimas bertujuan untuk meningkatkan jumlah fasilitas pada warga masyarakatkurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan peri-
urban. Dengan Pamsimas, diharapkan mereka dapat mengakses pelayanan air minum dan
sanitasi yang berkelanjutan serta meningkatkan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat.Penerapan program ini dalam rangka mendukung pencapaian target MDGs (sektor air minum
dan sanitasi) melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan pembangunan berbasis
masyarakat.
Program Pamsimas I dilaksanakan pada tahun 2008 sampai tahun 2012 di 110 Kabupaten/Kota
dari 15 Provinsi. Pamsimas I berhasil diterapkan pada 6.845 (enam ribu delapan ratus empatpuluh lima) desa, terdiri dari 6.262 (enam ribu dua ratus enam puluh dua) desa reguler dan
sekitar 593 (lima ratus sembilan puluh tiga) desa replikasi.
Program Pamsimas II dilaksanakan pada tahun 2013 sampai dengan 2016. Program Pamsimas IIditargetkan akan dilaksanakan di sekitar 5000 desa di 32 provinsi di 220 Kab/Kota.
8. Bagaimana seharusnya pengelolaan limbah rumah sakit?
Pengolahan limbah RS Pengelolaan limbah RS dilakukan dengan berbagai cara. Yang
diutamakan adalah sterilisasi, yakni berupa pengurangan (reduce) dalam volume, penggunaan
-
5/20/2018 tugas ikm
6/7
kembali (reuse) dengan sterilisasi lebih dulu, daur ulang (recycle), dan pengolahan (treatment)
(Slamet Riyadi, 2000).
Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan
kodifikasi dengan warna yang menyangkut hal-hal berikut :
1. Pemisahan Limbah
- Limbah harus dipisahkan dari sumbernya
- Semua limbah beresiko tinggi hendaknya diberi label jelas
- Perlu digunakan kantung plastik dengan warna-warna yang berbeda yang menunjukkan
kemana kantong plastik harus diangkut untuk insinerasi aau dibuang (Koesno Putranto. H, 1995).
2. Penyimpanan Limbah
Dibeberapa Negara kantung plastik cukup mahal sehingga sebagai gantinya dapat digunkanan
kantung kertas yang tahan bocor (dibuat secara lokal sehingga dapat diperloleh dengan mudah)kantung kertas ini dapat ditempeli dengan strip berwarna, kemudian ditempatkan ditong dengan
kode warna dibangsal dan unit-unit lain.
3. Penanganan Limbah
- Kantung-kantung dengan warna harus dibuang jika telah terisi 2/3 bagian. Kemudian diikiatbagian atasnya dan diberik label yang jelas
- Kantung harus diangkut dengan memegang lehernya, sehingga jika dibawa mengayunmenjauhi badan, dan diletakkan ditempat-tempat tertentu untuk dikumpulkan
- Petugas pengumpul limbah harus memastikan kantung-kantung dengan warna yang samatelah dijadikan satu dan dikirimkan ketempat yang sesuai
- Kantung harus disimpan pada kotak-kotak yang kedap terhadap kutu dan hewan perusak
sebelum diangkut ketempat pembuangan.
4. Pengangkutan limbah
Kantung limbah dipisahkan dan sekaligus dipisahkan menurut kode warnanya. Limbah bagianbukan klinik misalnya dibawa kekompaktor, limbah bagian Klinik dibawa keinsenerator.
Pengangkutan dengan kendaraan khusus (mungkin ada kerjasama dengan dinas pekerja umum)
kendaraan yang digunakan untuk mengangkut limbah tersebut sebaiknya dikosongkan dan
dibersihkan setiap hari, jika perlu (misalnya bila ada kebocoran kantung limbah) dibersihkandengan menggunakan larutan klorin.
5. Pembuangan limbah
-
5/20/2018 tugas ikm
7/7
Setelah dimanfaatkan dengan konpaktor, limbah bukan klinik dapat dibuang ditempat
penimbunan sampah (Land-fill site), limbah klinik harus dibakar (insenerasi), jika tidak mungkin
harus ditimbun dengan kapur dan ditanam limbah dapur sebaiknya dibuang pada hari yang samasehingga tidak sampai membusuk.
(Bambang Heruhadi, 2000).
Rumah sakit yang besar mungkin mampu memberli inserator sendiri, insinerator berukuran kecil
atau menengah dapat membakar pada suhu 1300-1500 C atau lebih tinggi dan mungkin dapatmendaur ulang sampai 60% panas yang dihasilkan untuk kebutuhan energi rumah sakit. Suatu
rumah sakit dapat pula mempertoleh penghasilan tambahan dengan melayani insinerasi limbah
rumah sakit yang berasal dari rumah sakit yang lain. Insinerator modern yang baik tentu sajamemiliki beberapa keuntungan antara lain kemampuannya menampung limbah klinik maupun
limbah bukan klinik, termasuk benda tajam dan produk farmasi yang tidak terpakai lagi.
Jika fasilitas insinerasi tidak tersedia, limbah klinik dapat ditimbun dengan kapur dan ditanam.
Langkah-langkah pengapuran (Liming) tersebut meliputi sebagai berikut :
1. Menggali lubang, dengan kedalaman sekitar 2,5 meter
2. Tebarkan limbah klinik didasar lubang samapi setinggi 75 cm
3. Tambahkan lapisan kapur4. Lapisan limbah yang ditimbun lapisan kapur masih bisa ditanamkan samapai ketinggian
0,5 meter dibawah permukaan tanah
5. Akhirnya lubang tersebut harus ditutup dengan tanah
(Setyo Sarwanto, 2003).
Perlu diingat, bahan yang tidak dapat dicerna secara biologi (nonbiodegradable), misalnyakantung plastik tidak perlu ikut ditimbun. Oleh karenanya limbah yang ditimbun dengan kapur
ini dibungkus kertas. Limbah-limbah tajam harus ditanam.
Limbah bukan klinik tidak usah ditimbun dengan kapur dan mungkin ditangani oleh DPU atau
kontraktor swasta dan dibuang ditempat tersendiri atau tempat pembuangan sampah umum.Limbah klinik, jarum, semprit tidak boleh dibuang pada tempat pembuangan samapah umum.
Semua petugas yang menangani limbah klinik perlu dilatih secara memadai dan mengetahuilangkah-langkah apa yang harus dilakukan jika mengalami inokulasi atau kontaminasi badan.
Semua petugas harus menggunakan pakaian pelindung yang memadai, imunisasi terhadap
hepatitis B sangat dianjurkan dan catatan mengenai imunisasi tersebut sebaiknya tersimpandibagian kesehatan kerja (Moersidik. S.S, 1995).
9. Bagaimana pengelolaan sampah di berbagai kota di Indonesia?