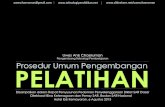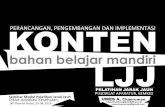PENGEMBANGAN PROGRAM PELATIHAN PB
description
Transcript of PENGEMBANGAN PROGRAM PELATIHAN PB
1
Pengembangan Program Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Relawan
Oleh Drs. Wyn W. Purwinto, MA, CAS-Ed /01-12-2014/
KEBIJAKAN
1. Instansi atau organisasi atau individu mana saja yang mensosialisasikan aturan hukum dan perundang-undangan terkait mitigasi bencana, sehingga relawan dapat terlibat aktif dan selaras dalam pelaksanaan mitigasi sesuai ketetapan hukum yang berlaku?
2. Apakah relawan dan/atau pengurus organisasi relawan sudah pernah membaca: - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
3. Apakah ada peraturan lokal tentang penanggulangan bencana yang dikeluarkan oleh BPBD, Bupati, Camat, Kepala Desa/Lurah, Kepala Dinas, Pimpinan Militer dan Kepolisian, Kepala Lembaga Kependidikan, Ketua Yayasan atau Organisasi Swasta?
4. Apakah ada aturan atau pedoman informal (tertulis maupun tidak, norma sosial, local
wisdom) dalam masyarakat setempat tentang penanggulangan bencana di wilayahnya? MITIGASI
Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Beberapa prinsip dasar yang diterapkan dalam upaya peningkatan mitigasi bencana, adalah: a. Kecepatan dan ketepatan mitigasi bencana; Kecepatan mitigasi dipengaruhi oleh peralatan dan petugas yang terlatih. Sedangkan ketepatan mitigasi terkait dengan cara yang digunakan sesuai dengan karakter suatu daerah. b. Prioritas pelaksanaan mitigasi bencana; Tingkat prioritas perlu dilakukan karena pemerintah mempunyai keterbatasan alokasi dana dan alokasi waktu. Tingkat prioritas ditentukan berdasarkan kondisi lapangan. c. Koordinasi dan keterpaduan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan mitigasi bencana;
d. Berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya mitigasi bencana;
e. Transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan mitigasi;
f. Penerapan tindakan kemitraan antar para pemangku kepentingan dan segala upaya pengembangannya;
2
g. Pemberdayaan sumber daya yang ada untuk peningkatan mitigasi;
h. Menjunjung tinggi persamaan hak dan kewajiban atas semua pihak yang terlibat dalam peningkatan mitigasi;
i. Pemberian bantuan atau sumbangan untuk peningkatan mitigasi banjir bandang tidak boleh dikaitkan dengan agama atau keyakinan tertentu. Peranan Kementerian Pendidikan dalam mitigasi bencana:
membuat kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan kebencanaan yang dimasukkan ke dalam kurikulum resmi pendidikan sekolah. Dengan hal ini diharapkan masyarakat dapat mengenal dan paham tentang bencana sejak usia dini;
menjamin terlaksananya pendidikan dan proses belajar-mengajar;
menyediakan sarana atau fasilitas penunjang proses belajar-mengajar di daerah yang terkena bencana;
menyediakan buku-buku yang diperlukan dalam proses belajar-mengajar, baik saat bencana terjadi ataupun setelah terjadinya bencana.
Peran Pemerintah Daerah dalam mitigasi bencana:
menyusun rencana penanggulangan bencana daerah, meliputi: mitigasi, kegiatan pra bencana, tanggap darurat dan kegiatan paska bencana;
menjamin konsistensi antara rencana nasional penanggulangan bencana dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk bencana;
meningkatkan kesiapsiagaan dan kelancaran penyediaan logistik;
meningkatkan kesiapsiagaan Muspida setempat. pengaturan tentang kedudukan, tugas dan fungsi BPBD yang ditetapkan dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri. Peran Kementerian Kesehatan dalam mitigasi bencana:
menjamin layanan kesehatan pada saat terjadi bencana, untuk pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena dan terimbas bencana, dan pemenuhan kebutuhan sarana kesehatan (seperti: mandi cuci kakus, air bersih, air minum, dll);
memberikan bantuan pendampingan dan pemantauan pemulihan kesehatan bagi masyarakat dan pengungsi yang menjadi korban bencana.
Peran Kementerian Sosial dalam mitigasi bencana:
pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan untuk para pengungsi yang menjadi korban bencana;
penyediaan shelter bagi korban bencana bekerja sama dengan instansi lain dan masyarakat setempat.
Peran Kementerian Pekerjaan Umum dalam mitigasi bencana:
a. Dirjen Sumber Daya Air: penanggulangan darurat dan rehabilitasi kerusakan bendungan, sarana pendukung air
bersih, sarana pendukung air minum, akibat bencana banjir;
3
perencanaan pengelolaan sumber daya air wilayah sungai;
membantu pemeliharaan wilayah sungai (pengerukan dasar sungai akibat pendangkalan karena banjir, membangun dinding sungai yang rusak, dlsb) dan kualitas air;
pembinaan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya air. b. Dirjen Cipta Karya: penanggulangan darurat dan rehabilitasi kerusakan sarana dan fasilitas umum akibat
bencana, seperti: kantor desa, sekolah, poliklinik, tempat ibadah, mandi cuci kakus, dll; perencanaan pengelolaan sarana dan bangunan fasilitas umum;
Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mitigasi bencana:
menetapkan status dan tingkatan bencana di wilayah kerjanya, dilengkapi informasi rinci yang berguna untuk peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
pengendalian pengumpulan dan bantuan berupa uang atau barang yang akan disalurkan untuk para korban di daerah yang terkena dampak bencana;
sebagai pelaksana kebijakan BNPB di daerah otonom. Peran BASARNAS dalam mitigasi bencana:
pencarian dan penyelamatan korban bencana, bekerjasama dengan unsur-unsur masyarakat dan instansi lainnya, seperti unit SAR yang tergabung di bawah perusahaan swasta di daerah;
membantu dan memberi masukan kepada BNPB/ BPBD dalam mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pencarian dan penyelamatan (SAR) di lokasi yang terkena bencana;
bekerjasama dengan Pramuka, Tagana, PMI, Polri, TNI dan tim infokom (ORARI, RAPI, dlsb), dalam upaya penyelamatan korban bencana, serta pemulihan paska bencana, dibawah koordinasi BNPB/BPBD atau pihak lain yang ditunjuk untuk mewakili.
Peranan masyarakat dalam mitigasi bencana (community-based disaster management) banjir sangat diperlukan pada tahap mitigasi atau pra-bencana, saat bencana atau tanggap darurat, dan pasca bencana atau rehabilitasi dan rekonstruksi. Segala aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat dalam mitigasi bencana dilakukan di bawah koordinasi BPBD atau Muspida (musyawarah pimpinan daerah) / Muspika (musyawarah pimpinan kabupaten/kota) setempat. Penguatan ketahanan sosial di masyarakat perlu dilakukan untuk mempermudah koordinasi dan alih pengetahuan tentang bencana, serta untuk menghindari perselisihan dan perpecahan akibat provokasi pihak-pihak tertentu saat pelaksanaan mitigasi. Ketahanan sosial masyarakat yang baik bermanfaat untuk membantu pelaksanaan mitigasi saat proses penyelamatan dan pemulihan paska bencana. Tokoh masyarakat atau tokoh agama umumnya mempunyai pengaruh yang kuat dalam menciptakan penguatan ketahanan sosial masyarakat. Oleh sebab itu, segala bentuk mitigasi kedaruratan perlu melibatkan tokoh agama atau tokoh masyarakat setempat. Pengelolaan lingkungan hidup amat penting bagi mengurangi risiko bencana. Tindakan manusia yang salah dalam mengelola linkungannya bisa memicu terjadinya bencana banjir.
4
Oleh karena itu, cara-cara pengelolaan lingkungan hidup untuk mengurangi risiko bencana banjir perlu disosialisasikan, dimana beberapa di antaranya adalah:
Pengelolaan hutan secara terpadu dengan tidak melakukan penebangan hutan secara liar atau mengurangi alih fungsi hutan;
Penebangan vegetasi dapat meniadakan akar-akar tanaman yang dapat mengikat dan mempertahankan massa tanah, akibatnya tanah menjadi rawan longsor. Banjir bandang dapat terjadi secara tiba-tiba saat terjadi hujan deras yang mengakibatkan longsor dan aliran lumpur di permukaan;
Pengembangan dan pengelolaan area pertambangan yang tidak terkendali umumnya merupakan pertambangan rakyat. Area yang semula stabil akan menjadi rawan longsor sehingga berpotensi terjadi banjir bandang bila terjadi hujan lebat di lokasi tersebut.
Menjaga dan melestarikan vegetasi yang sesuai dengan daya dukung lingkungannya.
TANGGAP DARURAT
Tanggap darurat bencana: Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana. Sistem peringatan dini / early warning system (EWS): Merupakan sebuah rangkaian penyampaian informasi hasil prediksi suatu ancaman kepada masyarakat, sebelum terjadinya sebuah peristiwa yang dapat menimbulkan resiko, yang bertujuan untuk memberikan peringatan agar penerima informasi dapat segera siap siaga dan bertindak sesuai kondisi, situasi dan waktu yang tepat. Prinsip utamanya adalah memberikan informasi yang cepat, akurat, tepat sasaran, mudah diterima, mudah dipahami, terpercaya dan berkelanjutan. Contoh: di desa bisa menggunakan sound system milik masjid atau mushola dan kentongan. Evakuasi darurat: Kegiatan perpindahan langsung dan cepat dari orang-orang yang menjauh dari ancaman atau kejadian yang sebenarnya dari bahaya menuju lokasi aman atau shelter tertentu. Sumber daya manusia: Tenaga manusia yang digunakan untuk menyelamatkan orang-orang yang terkena ancaman bahaya. Tenaga manusia berasal dari warga masyarakat setempat yang peduli dan terlatih, kelompok relawan, tim penanggulangan bencana dari pemerintah maupun militer dan polisi. Peralatan & sarana: Segala bentuk peralatan dan sarana yang bisa digunakan dalam penanggulangan bencana yang telah disiapkan oleh warga masyarakat dan tim penanggulangan bencana.
5
REHABILITASI & REKONSTRUKSI Rehabilitasi Perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Rekonstruksi Pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana. ======================================================================= ISTILAH & DEFINISI: Berikut ini merupakan penjabaran tentang istilah-istilah beserta definisinya masing-masing yang digunakan dalam pedoman ini. 1 aliran debris suatu tipe aliran gerakan massa bahan rombakan (debris) dengan kandungan angkutan yang sangat besar, berbutir kasar, non-kohesif, terdiri dari material berbutir kecil sampai besar seperti pasir, kerikil, bebatuan kecil dan batu-batu besar (sand, gravel, cobbles, dan boulders). 2 ancaman bencana suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana. 3 apex lokasi titik perpindahan kecuraman dasar dari alur hulu ke alur hilirnya yang menjadi lebih landai. 4 banjir peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai. 5 banjir bandang
Deskripsi: Banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba, karena meluapnya debit yang melebihi kapasitas aliran alur sungai oleh konsentrasi cepat hujan dengan intensitas tinggi serta sering membawa aliran debris bersamanya atau runtuhnya bendungan alam, yang terbentuk dari material longsoran gelincir pada area hulu sungai. Banjir bandang terbentuk beberapa waktu setelah hujan lebat (dalam kisaran waktu beberapa menit sampai beberapa jam) yang terjadi dalam waktu singkat di sebagian daerah aliran sungai (DAS) atau alur sungai yang sempit di bagian hulu.
6
Karakteristik Banjir Bandang: - memiliki debit puncak yang melonjak dengan tiba-tiba dan menyurut kembali dengan cepat;
- memiliki volume dan kecepatan aliran yang besar;
- memiliki kapasitas transpor aliran dan daya erosi yang sangat besar sehingga dapat membawa material hasil erosi (kaki tebing, dasar alur sungai, bahan rombakan bendungan alam) menuju arah hilir;
- aliran yang membawa material debris dapat menimbulkan bencana sedimen di daerah hilir setelah titik apex.
Penyebab terjadinya banjir bandang: - Terkumpulnya curah hujan lebat yang jatuh dalam durasi waktu yang singkat pada (sebagian) DAS alur hulu sungai, dimana kemudian volume air terkumpul dalam waktu cepat ke dalam alur sungai sehingga menimbulkan lonjakan debit yang besar dan mendadak melebihi kapasitas aliran alur hilirnya;
- Runtuhnya bendungan, tanggul banjir atau bendungan alam yang terjadi karena tertimbunnya material longsoran pada alur sungai.
6 bendungan bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (tailing), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk. 7 bottleneck leher botol atau penyempitan jalur 8 daerah aliran sungai (DAS) suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. 9 data primer data yang diperoleh langsung dari objeknya atau merupakan hasil pengukuran langsung. 10 data sekunder data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan atau data pendukung yang diperoleh dari studi literatur, peta dan hasil dari berbagai publikasi. 11 evakuasi darurat kegiatan perpindahan langsung dan cepat dari orang-orang yang menjauh dari ancaman atau kejadian yang sebenarnya dari bahaya. 12 hunian sementara (huntara/shelter) penampungan sementara bagi korban bencana alam beserta sarana dan prasarana pendukungnya baik melalui temporary shelter, semi permanents shelter, dan permanent shelter dengan menggunakan prinsip-prinsip penanggulangan bencana.
7
13 longsor suatu proses perpindahan massa tanah atau batuan dengan arah miring dari kedudukan semula (sehingga terpisah dari massa yang mantap), karena pengaruh gravitasi, serangan arus, gempa, dan lain-lain, dengan jenis gerakan berbentuk rotasi dan translasi. 14 mitigasi serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. 15 pemangku kepentingan / stakeholder segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang sedang diangkat. 16 pemerintah daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 17 pemerintah pusat Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 18 penataan ruang suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 19 pengungsi orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum bisa dipastikan sebagai akibat dampak buruk terjadinya bencana atau musibah. 20 peringatan dini serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. 21 rawan bencana kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. 22 risiko bencana potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. 23 sistem peringatan dini / early warning system (EWS) merupakan sebuah rangkaian penyampaian informasi hasil prediksi suatu ancaman kepada masyarakat, sebelum terjadinya sebuah peristiwa yang dapat menimbulkan resiko, yang bertujuan untuk memberikan peringatan agar penerima informasi dapat segera siap siaga dan bertindak sesuai kondisi, situasi dan waktu yang tepat. Prinsip utamanya adalah memberikan informasi yang cepat, akurat, tepat sasaran, mudah diterima, mudah dipahami, terpercaya dan berkelanjutan.
8
24 sungai alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. 25 tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarananya. 26. tsunami Kata tsunami berasal dari bahasa Jepang. ‘tsu’ berarti pelabuhan dan ‘name’ berarti gelombang. Sehingga secara umum diartikan sebagai gelombang/ombak yang besar di pelabuhan. Tsunami dapat diartikan sebagai gelombang laut yang disebabkan oleh gempa bumi dengan pusat di bawah laut, letusan gunung api bawah laut, longsor di bawah laut, atau hantaman meteor di laut. KEPUSTAKAAN Buku Saku: Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana. 2012. BNPB. Disaster Preparedness: A Checklist. 2004. The National Crime Prevention Council, USA. Flood Action Guide by Emergency Management Australia Pedoman Penanggulangan Bencana – Bidang Ke-PU-an. Kementerian Pekerjaan Umum. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Sistem Nasional Penanggulangan Bencana. BNPB, Direktorat Pengurangan Risiko Bencana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
. ======================================================================= Drs. Wyn W. Purwinto, MA, CAS-Ed, adalah alumnus Universitas Indonesia, Michigan State University, dan Syracuse University, U.S.A.,
yang telah mengikuti sejumlah kursus Manajemen Kebencanaan dari Emergency Management Institute (EMI), Federal Emergency
Management Agency (FEMA), Department of Homeland Security, U.S.A., dan sejak tahun 2004 telah melatih cluster informasi dan
komunikasi (infokom) kedaruratan bagi sejumlah tim atau unit penanggulangan bencana di dalam maupun luar negeri.
9
Lampiran tentang hukum kebencanaan:
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA
No. 24 Tahun 2007 BAB I
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 2. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. 3. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. 4. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. 5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. 6. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
7. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. 8. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
10
9. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. 10. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. 11. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. 12. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana. 13. …