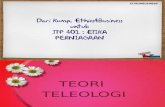Pendidikan Moral Kita
-
Upload
ziyyaelhakim -
Category
Documents
-
view
906 -
download
4
Transcript of Pendidikan Moral Kita
PENDIDIKAN MORAL KITA: Pengetahuan Normative vs RasionalOleh Rum RosyidReformasi dalam pelbagai bidang, utamanya yang menyangkut perubahan tatanan hukum, politik, dan ekonomi telah menjadi wacana yang hingga saat ini terus bergulir. Yang umumnya mengemuka adalah perbincangan yang mengarah pada perlunya perombakan sistem hukum, undang-undang kepartaian, peraturan-peraturan atau perundang-undangan untuk menyelenggarakan pemilu, perangkat hukum untuk mengatur kehidupan ekonomi, sosial, dan politik, serta gencarnya retorika (bukan realita) pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Meskipun disinggung pula perlunya reformasi dalam sektor pendidikan, namun gagasan itu seperti hilang ditelan hiruk pikuknya parade gagasan reformasi hukum, ekonomi, dan politik. Di sela-sela gencarnya suara reformasi di pelbagai bidang itu sayup-sayup terdengar perlunya reformasi moral, akhlak, dan yang serupa nilai maknanya dengan kata-kata ini. Umumnya, gagasan semacam ini terlontar dari kalangan agamawan, moralis, dan pendidik. Argumen yang dikemukakan antara lain: krisis besar yang melanda bangsa ini sesungguhnya bermuara pada terabaikannya nilai-nilai moral, edukasional, dan keagamaan dalam kehidupan nyata. Para orang tua dinilai gagal memberikan tuntunan nilai kepada anak. Para guru dianggap gagal menanamkan budi pekerti dan hanya menitikberatkan pada aspek pengetahuan. Kaum agamawan dianggap terlampau mengajarkan dogma-dogma yang sulit diterjemahkan dalam perilaku keseharian. Ini mengakibat kan hampir seluruh sendi kehidupan bermasyarakat mengalami penyimpangan karena terkontaminasi oleh cara-cara hidup yang tidak benar di masyarakat yang telah menjadikan penyimpangan sebagai kebiasaan.
Dalam Undang-Undang RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1, diungkapkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah: “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara” (UU RI No 20 Tahun 2003) dari defenisi pendidikan tersebut, dengan jelas terungkap bahwa pendidikan indonesia adalah pendidikan yang usaha sadar dan terencana, untuk mengembangkan potensi individu demi tercapainya kesejahteraan pribadi, masyarakat dan NegaraLantas sekarang ada banyak permasalahan yang timbul dari UU ini. Benarkah kita telah menyelenggarakan pendidikan? Lantas, bagaimana menjelaskan tindakan premanisme, korup, asusila, dan tindakan amoral dan melanggar hukum lainnya yang justru dilakukan oleh “orang-orang terdidik” dan dari “institusi-institusi dan lembaga terhormat” di negeri kita? Dimana letak kesalahan pendidikan selama ini?Dalam menyikapi realitas pendidikan sebagaimana disinggung, menarik untuk dikaji pula sebuah sikap ”setengah hati” bangsa kita. Di tengah konsensus bahwa sumber krisis berkepanjangan yang dialami bangsa Indonesia adalah krisis moral, tapi krisis ini tak kunjung usai. Disaat seluruh masyarakat dunia sibuk dengan krisis global kita pun ikut membicarakannya padahal ada krisis moral yang lebih parah lagi imbasnya yang bisa menjadi bom waktu bagi bangsa ini yang akan meledak dalam waktu tertentuBelum lama ini wajah pendidikan indonesia kembali tercorengkan oleh komponen pendidikan itu sendiri. Ada kasus seorang remaja yang menggadaikan harga diri untuk
memenuhi kebutuhan ekonomi sekolah. Ada kasus seorang wakil kepala sekolah yang melakukan pelecehan terhadap siswanya padahal Seorang guru yang seharusnya menjadi teladan, memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap muridnya malah membuat onar dengan melakukan hal yang tidak pantas dilakukan. Semua ini terjadi di dunia pendidikan kita.Disisi lain ada sebuah klinik dokter yang menjadi tempat aborsi, telah banyak janin yang tak berdosa mereka bunuh. Bahkan indoneisa menjadi negara yang paling banyak melakukan aborsi. Sangat ironis sekali jika kita lihat, klinik yang seharusnya menjadi tempat untuk menyelamatkan nyawa menjadi tempat pembunuhan dan yang lebih menyakitkan hati lagi hal ini dilakukan oleh dokter yang nota bennya sebagai orang terdidik yang telah menghabiskan uang puluhan juta ketika menempuh pendidikannya.
Krisis besar yang menimpa bangsa Indonesia bisa jadi karena telah membudayanya praktik penyimpangan semacam ini. Tulisan ini bertolak dari argumen yang mengemukakan bahwa reformasi moral merupakan suatu keharusan untuk melandasi reformasi pada dimensi apapun, lebih-lebih pada sektor pendidikan. Ini mengingat bahwa jauh sebelum reformasi digulirkan, masalah-masalah moral sudah menjadi persoalan yang banyak menyita perhatian, terutama dari pendidik, alim ulama, pemuka masyarakat, dan orang tua. Meskipun usaha untuk mengatasi masalah moral telah banyak dilakukan, namun hasilnya masih belum menggembirakan. Seperti telah dikemukakan Zakiah Daradjat lebih dua puluh tahun lalu (1977), usaha untuk menanggulangi kemerosotan moral telah banyak dilakukan, baik oleh lembaga keagamaan, pendidikan, sosial, dan instansi pemerintah. Namun kemerosotan moral semakin menjadi-jadi, tidak saja terbatas pada kota besar melainkan juga sampai ke pelosok-pelosok desa terpencil. Masalah-masalah moral yang serius dihadapi oleh bangsa Indonesia antara lain menyangkut persoalan kejujuran, kebenaran, keadilan, penyelewengan, adu domba, fitnah, menipu, mengambil hak orang lain, menjilat dan perbuatan-perbuatan maksiat lain. Lihat saja kerusuhan yang secara sporadic susul menyusul di republik ini yang secara gamblang memperlihatkan praktik-praktik penyimpangan moral yang akut.
Apabila tidak ada provokator yang "mengobok-obok" suasana dengan menebarkan benih kerusuhan antarkelompok niscaya tidak akan terjadi permusuhan bernuansa SARA seperti yang terjadi di Ambon. Begitu juga dengan masih mengedepannya masalah tiga serangkai kolusi-korupsi-nepotisme. Jika saja nilai-nilai kejujuran dan nilai-nilai moralitas yang menunjung tinggi penghargaan serta kepedulian pada nasib sesama telah berurat berakar pada diri manusia Indonesia ketiganya tidak akan menjadi masalah besar yang memerlukan penanganan secara nasional. Karena itulah, pendidikan moral untuk menginternali sasikan nilai-nilai kejujuran dan kebenaran perlu mendapat perhatian lebih serius agar bangsa ini dapat terselamatkan dari krisis multidimensional berkepanjangan. Esensi Mengapa pendidikan moral perlu dikedepankan? Adanya panutan nilai, moral, dan norma dalam diri manusia dan kehidupan akan sangat menentukan totalitas diri individu atau jati diri manusia, lingkungan sosial, dan kehidupan individu. Oleh karena itu, pendidikan nilai yang mengarah pada pembentukan moral yang sesuai dengan norma-norma kebenaran menjadi sesuatu yang esensial bagi pengembangan manusia utuh dalam konteks sosialnya. Ini mengingat bahwa dunia afektif yang ada pada setiap manusia harus
selalu dibina secara berkelanjutan, terarah, dan terencana sehubungan dengan sifatnya yang labil dan kontekstual.
Jika kita kembali melihat penomena ini ada banyak penyebab yang melatar belakangi terjadinya segala tindakan amoral pada pendidikan kita sehigga krisis moral ini terus berlanjut. Pertama, didalam dunia pendidikan kita sekolah yang faforit adalah sekolah yang dapat menghasilkan kelulusan para peserta didiknya dengan nilai yang tinggi, nilai yang lebih berdasarkan pada Intelegensi semata sehingga guru dan siswa berpacu untuk menjadi yang terbaik dengan lebih megutamakan IQ semata. Tanpa disadari ternyata hal ini menjadi salah satu penyebab krisis moral yang melanda pendidikan kita karena sekolah-sekolah lebih mengutamakan kelulusan dengan nilai tinggi namun dari sisi spritualnya tidak begitu diperhatikan padahal jika kita bercermin kembali pada UU No, 20 Tahun 2003 sebagaimana diatas kita akan melihat bahwa tujuan pendidikan itu adalah pembinaan dengan kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Jika kita ambil perbandingan maka terlihat jelas bahwa pendidikan kita yang sebenarnya adalah lebih berorientasi pada pembentukan akhlak dan moral.Kedua, internalisasi nilai-nilai agama yang kurang dilakukan oleh para guru dan civitas akademika serta kurangnya keteladanan dari para pendidik. Seorang guru yang yang baik adalah pendidik yang di gugu dan ditiru oleh para peserta didik. Guru seharusnya memberikan contoh baik kepada para peserta didiknya bukan malah sebaliknya memberikan contoh yang buruk. Bagaimana mungkin para siswa akan terdidik dengan baik jika pendidiknya tidak memiliki akhlak yang baik. Bak kata pepatah ” guru kencing bediri murid kencing berlari”. Proses pendidikan yang dilakukan saat ini hanya berkutat pada masalah pengajaran bukan pendidikan moralKetiga, profesionalisme guru. Guru adalah kompenen yang penting yang menentukan arah pendidikan, profesionalisme guru sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tujuan pendidikan. Seorang guru bukan hanya seorang pengajar yang hanya mengajarkan materi sesuai kurikulum, namun dia harus mendidik para peserta didik dengan nilai-nilai keimanan dan moral yang baik sehingga tujuan pendidikan itu terlaksana dengan baik, tapi kenyataan yang terjadi saat ini justru sebaliknya. Sebagian kecil Guru hanya melaksanakan tugasnya sebatas mengajar materi sesuai kurikulum saja sementara didikan moralnya serta pembinaannya sangat kurang sekali sehingga hal inilah yang menjadi pemicu kerusakan moral didunia pendidikan kita. Untuk itu hendaknya ada uji kompetensi yang dilakukan agar tujuan pendidikan kita bisa terlaksana.Keempat, Titel dan Gelar menjadi target sehingga tanggung jawab Ilmiah terabaikan. Hal ini banyak terjadi di daerah-daerah dan kampus-kampus. Sebagian besar mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi banyak yang hanya ingin mengambil gelar dan titel bahkan ada yang malakukan berbagai cara untuk mendapatkan gelar tersebut meski keluar uang jutaan rupiah. Apa yang akan kita katakan tentang hal ini? Apakan ini sebuah kemajuan bagi pendidikan kita? Tentunya ini adalah kemunduran bagi kita dan krisis moral di dunia pendidikan kita.
Sasaran pendidikan nilai pada umumnya dapat diarahkan untuk (a) membina dan menanamkan nilai moral dan norma, (b) meningkatkan dan memperluas tatanan nilai
keyakinan seseorang atau kelompok, (c) meningkatkan kualitas diri manusia, kelompok atau kehidupan, (d) menangkal, memperkecil dan meniadakan hal-hal yang negatif, (e) membina dan mengupayakan terlaksananya dunia yang diharapkan (the expected world), (f) melakukan klarifikasi nilai intrinsik dari suatu nilai moral dan norma dan kehidupan secara umum (Kosasih Djahiri, 1992). Untuk dapat melakukan pendidikan moral tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah oleh guru saja. Pendidikan moral dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan dimana saja. Meskipun demikian, umumnya disebut tiga lingkungan yang amat kondusif untuk melaksanakan pendidikan moral, yakni lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, dan lingkungan masyarakat.
Diantara ketiganya, merujuk pada Dobbert dan Winkler (1985), lingkungan keluarga merupakan faktor dominan yang efektif dan terpenting. Peran keluarga dalam pendidikan nilai adalah mendukung terjadinya proses identifikasi, internalisasi, panutan, dan reproduksi langsung dari nilai-nilai moral yang hendak ditanamkan sebagai pola orientasi dari kehidupan keluarga. Lingkungan keluarga dengan demikian menjadi lahan paling subur untuk menumbuh kembangkan pendidikan moral. Secara operasional, yang paling perlu diperhatikan dalam konteks pendidikan moral di lingkungan keluarga adalah penanaman nilai-nilai kejujuran dalam segenap aspek kehidupan keluarga. Contoh sikap dan perilaku yang baik oleh orang tua dalam pergaulan dan kehidupan mereka dapat menjadi teladan bagi anak-anaknya. Di samping itu, pendidikan moral harus dilaksanakan sejak anak masih kecil dengan jalan membiasakan mereka kepada peraturan-peraturan dan sifat-sifat yang baik, serta adil. Sifat-sifat tersebut tidak akan dapat difahami oleh anak-anak, kecuali dengan pengalaman langsung yang dirasakan akibatnya dan dari contoh orang tua dalam kehidupannya sehari-hari.
Pendidikan moral yang paling baik sebenarnya terdapat dalam agama, karena nilai-nilai moral yang dapat dipatuhi dengan kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dari luar, datangnya dari keyakinan beragama yang harus ditanamkan sejak kecil. Lingkungan pendidikan juga menjadi wahana yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan mental serta moral anak didik. Untuk itu, sekolah diharapkan dapat berfungsi sebagai kawasan yang sejuk untuk melakukan sosialisasi bagi anak-anak dalam pengembangan mental, moral sosial dan segala aspek kepribadiannya. Pelaksanaannya di kelas hendaknya dipertautkan dengan kehidupan yang ada di luar kelas. Pilar Reformasi Yang menjadi masalah adalah apabila lingkungan di masyarakat telah didominasi oleh praktik-praktik penyimpangan moral itu sendiri. Misalnya, masyarakat telah terbiasa mengeluarkan biaya pembuatan KTP, SIM, dan semacamnya lebih besar dari biaya yang seharusnya dibayar. Komentar-komentar atau penjelasan- penjelasan tokoh panutan masyarakat yang simpang siur dan menomordua kan nilai kejujuran bagaimanapun memberikan "pelajaran moral" yang tidak baik bagi masyarakat. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara pendidikan moral yang ditanamkan dalam lingkungan keluarga dan lingkungan pendidikan dengan praktik aktual yang terjadi di masyarakat. Lebih buruk lagi apabila ketiga lingkungan ini telah terkontaminasi satu sama lain. Terciptalah kondisi anomali yang menjadi muara dari segala krisis seperti yang saat ini mendera bangsa Indonesia.
Bertolak dari kondisi itu seharusnya makin menggugah kesadaran kita betapa pentingnya pendidikan moral bagi anak-anak dan betapa bahayanya mengabaikan pendidikan moral. Untuk itu, pendidikan moral perlu diarahkan menuju upaya-upaya terencana untuk menjamin moral anak-anak yang diharapkan menjadi warga negara yang cinta akan bangsa dan tanah airnya, dapat menciptakan dan memelihara ketenteraman dan kerukunan masyarakat dan bangsa di kemudian hari. Jalan panjang yang terutama harus ditempuh adalah memberdayakan pendidikan moral secara intensif di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Pendidikan moral dalam ketiga kawasan strategis ini harus diperhitungkan sebagai pilar penentu keberhasilan reformasi dalam pelbagai dimensi kehidupan. Dalam konteks ini, pendidikan moral menghendaki lahirnya generasi muda yang memiliki sejumlah bekal nilai baku yang positif sebagai landasan dan barometer kehidupan, serta lebih jauh lagi sebagai generasi penerus dan generasi reformis.
Reformasi dalam bidang apapun harus dipandu oleh nilai-nilai moral yang menjadi tuntunan hidup bersama dalam masyarakat. Ini mengisyaratkan bahwa perubahan melalui reformasi dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, pendidikan, maupun bidang-bidang lain tidak akan dapat terselenggara tanpa perbaikan mental dan moral terlebih dahulu. Untuk itulah, pendidikan moral harus diperhitungkan sebagai landasan titik tolak dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam aspek moralitas pergeseran terjadi pada pandangan masyarakat tentang konsep moralitas itu sendiri. Moralitas di sini dipahami sebagai konsep tentang moral atau kebaikan atau baiknya sesuatu yang telah dikonstruksi oleh masyarakat.
Ketika penjajah yang berkuasa di Indonesia, maka konsepsi tentang moral harus mengikuti konstruksi masyarakat penjajah. Sedangkan sebagaimana dijelaskan di depan bahwa ideologi para penjajah adalah materialisme-kapitalis, maka sesuatu atau seseorang dianggap baik dan bermoral ketika sesuatu itu bermanfaat dan berguna secara materiil. Seseorang dikatakan kurang moralitas dan nilainya di hadapan masyarakat ketika seseorang itu tidak mampu memberikan manfaat dan kegunaan secara materiil. Orang yang dianggap berhasil dan bermoral adalah seseorang yang telah memiliki jabatan, kekayaan, dan harta lebih dari orang tuanya. Demikianlah pergesaran yang terjadi sebagai akibat terjadinya penjajahan di Indonesia.
Pada masa penjajahan Jepang --yang merupakan Saudara Tua (karena sama-sama di benua Asia dengan Indonesia)—pendidikan tradisional mulai mendapatkan angin kemajuan. Namun, semua itu tidak ada artinya karena memang penjajahan Belanda sebagai salah satu bangsa Barat atau lebih dikenal dengan bangsa Barat telah menancapkan ideologi, politk, ekonomi, budaya, dan moralitas kepada masyarakat pribumi, maka angin segar tersebut tidak mampu dimanfaatkan secara maksimal. Dengan demikian pendidikan tradisional menjadi sangat sulit untuk kembali lagi ke posisi semula, yakni sebelum adanya penjajahan bangsa Barat.
Pendidikan yang Bermoral dan Mencerdaskan BangsaMemasuki masa kemerdekaan pendidikan Islam masih terus berkutat dengan sistem pendidikan modern (peninggalan Belanda). Sistem pendidikan ini dipelopori oleh para
tokoh pendidikan yang telah mengenyam sistem pendidikan Belanda atau Barat. Oleh karena itu, menjadi sangat masuk akal ketika sistem pendidikan nasional Indonesia berkiblat kepada sistem pendidikan Barat. Sistem pendidikan yang berkiblat pada sistem pendidikan Barat secara praktis dan teoritis berbeda dengan sistem pendidikan Islam tradisional. Dari sinilah kemudian terjadi pemisahan antara pendidikan tradisional yang dalam hal ini bias direpresentasikan oleh pendidikan Islam dan pendidikan modern yang dalam hal ini bias direpresentasikan oleh pendidikan nasional. Kedua sistem pendidikan ini merupakan sebuah hasil kompromi para founding father negeri ini.
Kompromi yang diambil para founding father negeri ini adalah bahwa pengabaian sistem pendidikan Islam tradisional akan sangat menyakitkan umat Islam. Mengingat jasa dan pengorbanan para ulama dan santri dari trilogi sistem pendidikan Islam tersebut di atas. Pertimbangan lainnya adalah agar umat Islam memiliki lembaga pendidikan khusus, sehingga mayoritas penduduk Indonesia tidak mengalami kekecewaan yang luar biasa kepada pemerintah. Oleh karena itu, pada masa kemerdekaan tepatnya pada 3 Januari 1946 didirikanlah Departemen Agama yang mengurusi urusan umat Islam. Meskipun pada dasarnya Departemen Agama ini mengurusi keperluan seluruh umat beragama di Indonesia, namun melihat latar belakang pendiriannya jelas untuk mengakomodasi kepentingan dan aspirasi umat Islam sebagai mayoritas penduduk negeri ini.
Dalam masalah pendidikan, kepentingan dan keinginan umat Islam juga ditampung di Departemen ini. Namun sangat disayangkan perhatian para pemimpin negeri ini kurang begitu besar terhadap pendidikan Islam di bawah naungan Depag ini. Hal ini terbukti dengan anggaran yang sangat berbeda dengan saudara mudanya yaitu pendidikan nasional. Perbedaan perhatian dengan wujud kesenjangan anggaran ini kemudian menyebabkan munculnya perbedaan kualitas pendidikan yang berbeda. Di satu sisi lembaga-lembaga pendidikan yang di bawah departemen pendidikan nasional mengalami perkembangan cukup pesat sementara pendidikan Islam yang berada di bawah payung Departemen Agama “terseok-seok” dalam mengikuti perkembangan zaman.
Sampai pada pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru pemisahan sistem dan pengelolaan pendidikan nasional dan pendidikan Islam masih dipertahankan. Artinya adalah bahwa pengelolaan pendidikan Islam masih mengalami nasib yang tidak bagus dibanding dengan saudara mudanya, pendidikan nasional. Walaupun secara substansial kedua sistem pendidikan tersebut oleh pemerintah Indonesia sendiri juga mengalami nasib yang sama buruknya, yaitu rendahnya anggaran pendidikan bila dibanding dengan negara-negara berkembang lain apalagi dibanding dengan negara-negara maju. Demikianlah nasib perjalanan pendidikan di Indonesia yang sampai saat ini masih menduduki rangking kurang begitu bagus dibanding negara-negara lainnya. Kurangnya perhatian pemerintah pusat dan menitikberatkan pembangunan pada sector ekonomi menyebabkan pembangunan jiwa dan mental bangsa menjadi termarjinalkan. Padahal pembangunan mental, jiwa, dan moral bangsa adalah sebuah keharusan dan keniscayaan sejarah yang tidak bisa ditawar-tawar, khususnya bagi bangsa Indonesia. Pendidikan moral bukan pendidikan ekonomi yang paling penting bagi bangsa Indonesia. Pendidikan ekonomi tanpa didukung dengan pendidikan moral yang kuat hanya akan memunculkan pemimpin-pemimpin yang berpenyakit kronis.
Masalah pendidikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini semakin memprihatinkan. Berbagai kegagalan pendidikan nasional yang dibangun khususnya semasa Orde Baru, kini secara nyata telah terbukti dan dapat dilihat dengan jelas. Semua orang, termasuk yang sangat awam sekalipun dapat melihat dan merasakan, bahkan banyak di antaranya yang terpuruk karena telah menjadi korban dari sistem pendidikan yang tidak bertanggung jawab.Sisi suram pendidikan, terutama yang menonjol adalah merosotnya moral bangsa dan negara. Kemerosotan itu kini telah terakumulasi, sehingga terjadi apa yang disebut dengan krisis moral, yaitu krisis yang sangat mendasar yang menjadi sumber utama dari terjadinya krisis multi dimensional yang tengah dihadapi.
Krisis moral bangsa dan negara yang disebabkan oleh masalah utama pendidikan itu terjadi sebagai dampak buruk dari penyelenggaraan pemerintahan pada masa Orde Baru yang sangat diwamai oleh dominannya nafsu kekuasaan, ketimbang membangun kehidupan bangsa dan negara yang bermoral. Pendidikan yang di dalamnya seharusnya sarat dengan muatan nilai-nilai moralitas dan berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, dipolitisasi sedemikian rupa hanya untuk kepentingan rezim yang berkuasa. Oleh sebab itu, maka tidak aneh jika hasil kebijakan pendidikan Orde Baru itu kini melahirkan krisis moral bangsa dan negara yang sedemikian parah dan sangat sulit dicarikan solusinya. Dengan kenyataan itu, mungkin dapat dibenarkan asumsi bahwa sistem pendidikan yang diterapkan pada masa Orde Lama atau bahkan pada masa penjajahan Belanda dahulu secara relatif lebih baik dan bertanggung jawab dibandingkan pada masa Orde Baru yang mempraktekkan pendidikan sebagai alat politik kekuasaan dan terjadinya proses pembodohan bangsa yang secara konstitusional bertentangan dengan maksud Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat yang menyatakan bahwa "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,....dst”. Tentu saja maksud mencerdaskan kehidupan bangsa di sini tidak berdiri sendiri, akan tetapi merupakan serangkaian tujuan yang saling terkait atau interdependen yang satu dengan lainnya.
Pesan moral yang terkandung dalam kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut, juga bermakna dalam kerangka tujuan memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Maknanya bahwa dengan melaksanakan pencerdasan kehidupan bangsa, maka berarti hal itu juga dimaksudkan untuk mencapai kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Inilah pesan moral yang menjadi kewajiban pemerintahan Negara Indonesia yang selama Orde Baru tidak menjadi perhatian dan bahkan diselewengkan. Sebagai contoh konkret ekses dari kebijakan pendidikan Orde Baru yang sangat memprihatinkan saat ini adalah terjadinya berbagai tindak kekerasan dan penyimpangan moral di kalangan pelajar dan generasi muda bangsa, seperti: tawuran, penodongan dan pembajakan bus kota yang dilakukan oleh oknum pelajar dan mahasiswa telah menjadi fenomena umum, khususnya di Jakarta.
Demikian juga dalam kasus narkoba, seks bebas, perkosaan di bawah umur dan pornografi secara umum telah melanda bahkan telah mewabah di kalangan generasi muda anak bangsa di hampir seluruh wilayah Nusantara.
Sungguhpun demikian harus disadari bahwa terjadinya krisis moralitas di kalangan pelajar dan generasi muda anak bangsa itu tentu saja bukan satu-satunya penyebab yang mewarnai krisis moral dalam bidang pendidikan. Sebab, krisis moralitas pelajar dalam tataran dan lingkup pendidikan yang lebih luas dan kompleks, hanyalah sebagian saja dan krisis moralitas bangsa secara keseluruhan. Kondisi itu terjadi tidak terlepas dari berbagai masalah mendasar, terutama seperti yang dijelaskan di atas adalah masalah ketidakbebasan pendidikan terhadap pengaruh kepentingan kekuasaan. Selain itu berkaitan juga dengan krisis profesionalisme dalam penanganan pendidikan, dan juga yang sangat berpengaruh adalah krisis keteladanan moral dari kalangan orang-orang tua generasi bangsa, para pemimpin, elite-elite politik, dan bahkan dari kalangan pendidik itu sendiri. Di samping juga adanya pengaruh lingkungan pergaulan dan keterbukaan sistem informasi yang cenderung bebas nilai. Kesemuanya itu merupakan bagian yang tidak terlepas dari bangunan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang tidak mempunyai visi pertanggungjawaban pendidikan, dan bahkan mengkondisionalkan terjadinya kejahatan dan pembejatan moral secara sistematis sebagaimana dijelaskan di atas.
Pembenahan Pendidikan Dalam upaya penataan ulang atau pembenahan menyeluruh terhadap sistem dan pelaksanaan pendidikan saat ini, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus memberikan prioritas utama pada pemulihan krisis moralitas bangsa dan negara yang berkaitan langsung dengan masalah tanggung jawab utama pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan harus mengacu kepada pencapaian tujuan dan pertanggungjawaban pendidikan yang bermoral dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, menumbuhkembangkan sikap-sikap kemandirian, dan menciptakan masyarakat pendidikan yang bermoral. Dengan adanya otonomi pendidikan, maka yang harus terwujud dan harus diwujudkan oleh pemerintah daerah dan penyelenggara pendidikan di daerah adalah lebih tertanganinya pendidikan secara profesional dan lebih terakomodasikannya muatan lokal, termasuk nilai-nilai moral kemasyarakatan setempat.Dalam rangka memenuhi tuntutan reformasi total sistem dan pelaksanaan pendidikan, termasuk memperbarui UU Pendidikan, maka diperlukan pengkajian yang lebih mendalam, mengembangkan keterlibatan sistem kerja dan jaringan stake holder pendidikan dalam pembahasan, penyusunan dan sosialisasi sistem dan program-program pendidikan yang akan diterapkan, dan tentu saja semuanya itu berpegang teguh pada prinsip-prinsip profesionalisme dan pertanggungjawaban moral yang tinggi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Menyadari akan kesalahan fundamental pemerintahan Orde Baru dalam memperlakukan pendidikan, maka tidak ada pilihan lain yang tepat dan harus dilakukan, kecuali melakukan penataan ulang sistem dan strategi pelaksanaan pendidikan ke depan, serta mempertegas keterkaitannya dengan aspek-aspek moralitas kemanusiaan, kebangsaan dan kenegaraan. yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang
Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam menetapkan tinjauan pendidikan perlu diperhatikan dasar konstitusional pendidikan dalam UUD 1945, BAB XIII tentang Pendidikan, Pasal 31 yang menyebutkan” (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-Undang".
Dalam upaya mencapai sasaran pendidikan yang diharapkan, yaitu yang utama adalah untuk membantu anak didik dan anggota masyarakat peserta pendidikan lainnya dalam mencapai kematangan pribadi dengan kualitas moral sebagaimana yang diharapkan di atas, sebagai wujud pengejawantahan dari pesan-pesan moral pendidikan yang bersumberkan pada Pembukaan UUD 1945. Pancasila dan UUD 1945. Selain itu juga perlu dirumuskan kembali suatu Undang-Undang Pendidikan yang mengakomodir tujuan-tujuan di atas sekaligus berorientasi pada sistem pendidikan universal dan penerapan otonomi pendidikan yang mengandung muatan-muatan lokal.Dengan memahami tujuan utama pendidikan dengan aspek-aspek moralitasnya itu, maka akan terbentuk pemahaman yang lebih komprehensif terhadap tujuan pendidikan dalam arti yang sangat ideal, sebagaimana yang dikemukakan oleh Edgar Faure bahwa tujuan pendidikan bukanlah pertama-tama menghasilkan "orang yang berguna" untuk kepentingan masyarakat, melainkan membentuk masyarakat pendidikan. Dalam konteks ini tentu saja Edgar Faure setuju, kalau masyarakat pendidikan yang dimaksud adalah masyarakat pendidikan yang bermoral dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Sedangkan visi pendidikan ke depan adalah sebagaimana yang telah digariskan oleh UNESCO, menegaskan bahwa pendidikan itu adalah mendidik anak untuk belajar berpikir, belajar hidup, belajar menjadi diri sendiri dan belajar untuk belajar hidup. Dengan kata lain bahwa pendidikan adalah merupakan sarana untuk menciptakan kemandirian yang sebenarnya kepada anak didik dan masyarakat pendidikan.Hal ini berkaitan dengan tuntutan yang menjadi tolok ukur keberhasilan seseorang, sebagaimana yang dikemukakan oleh Daniel Goleman dalam Working with Emotional Inteligence, antara lain: Tolok ukur baru yang menentukan keberhasilan seseorang dalam bekerja tidak hanya berdasarkan tingkat kepandaian atau pelatihan dan pengalaman, namun lebih pada seberapa efektif seseorang mengelola diri sendiri dan berhubungan dengan orang lain. Selanjutnya menurut Goleman, ada dua kecakapan emosional yang harus dimiliki, yaitu "kecakapan pribadi" dan "kecakapan sosial". Tentu saja, kedua kecakapan yang digolongkan Goleman itu dalam konteks kebutuhan bangsa dan negara Indonesia masih harus disertai dengan kecakapan dan tanggung jawab moral berbangsa dan bernegara.
Orang-orang ProfesionalBerkaitan dengan upaya pembenahan penanganan pendidikan yang selaras dengan pemahaman di atas, pada prinsipnya yang utama adalah membebaskan penanganan pendidikan itu dari berbagai pengaruh kepentingan negative atau sesaat kekuasaan. Pendidikan harus ditangani secara profesional, oleh orang-orang yang profesional dalam bidangnya dan mempunyai integritas moral terhadap kelangsungan moral bangsa dan
negara, sehingga penyelenggaraan pendidikan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, maka pada era pelaksanaan otonomi pendidikan sekarang ini, penyelenggaraan pendidikan yang bermoral dan ditangani secara profesional itu seharusnyalah semakin terjamin. Jangan sampai dengan adanya otonomi pendidikan, justru terjadi kemerosotan moral dan profesionalitas pendidikan. Kewenangan-kewenangan dalam menyelenggarakan pendidikan yang dimiliki oleh daerah dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada hakikatnya adalah kewenangan dalam upaya memajukan pendidikan yang mengacu kepada muatan-muatan lokal, termasuk muatan nilai-nilai moral kemasyarakatan setempat. Dalam hal ini, bukan berarti dengan pelaksanaan otonomi pendidikan, moral kebangsaan dan kenegaraan menjadi tidak diperlukan lagi. Justru sebaliknya semua nilai-nilai yang ada itu, termasuk nilai-nilai moral universal dan agama lebih menyatu dan semakin mendekatkan pelayanannya kepada kebutuhan moral kepribadian dan kemanusiaan. Otonomi pendidikan, diharapkan akan memunculkan kreativitas dan inisiatif dari penyelenggara pendidikan di daerah otonom, termasuk para pendidik yang berhubungan langsung dengan dunia pendidikan sekolah dan anak didik.Selain itu faktor keteladanan moral, baik secara internal dari para pendidik dan pembuat kebijakan pendidikan, maupun secara eksternal dari para pemimpin dan elite-elite politik bangsa dan negara, tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agama, serta para orang tua anak didik itu sendiri harus dapat menunjukkan suatu sikap dan perilaku moral yang patut diteladani. Mendidik melalui keteladanan adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya strategis mewujudkan tujuan pendidikan yang diharapkan. Paling tidak ada beberapa ciri kepribadian yang harus terbangun dan terpelihara dalam konteks keteladan ini, yakni: Pertama, pribadi yang selalu berkata dan berbuat benar, yaitu satunya kata dengan perbuatan atau konsisten. Pribadi yang jauh dari dusta atau kebohongan dan tidak pemah berbuat kemurkaan dan kezaliman. Kedua, pribadi yang tidak menyembunyikan segala sesuatu yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Jauh dari kemunafikan atau berpura-pura dan bersandiwara, dengan maksud menyembunyikan sesuatu yang harus disampaikan, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Sesuatu yang baik disampaikan kebaikannya, sedangkan yang buruk disampaikan keburukannya. Dan tidak sedikitpun yang terlupakan atau dengan sengaja dirahasiakan. Ketiga, pribadi yang jauh dan terhindar dari perbuatan salah dan menyalahkan orang lain. Keempat, pribadi yang dapat dipercaya karena kejujuran, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kelima, pribadi yang memiliki kecerdasan yang tinggi sehingga selalu bijaksana dalam perkataan dan perbuatan, tidak sombong, arogan, diktator, suka melecehkan, mengadu domba dan menghasut orang lain.
Materialisasi PendidikanKurikulum merupakan ’softwere’ yang paling fital dalam menghasilkan sebuah luaran pendidikan. Kurikulum pendidikan kita sebenarnya memang ’belum’ dirancang untuk menghasilkan produk luaran seperti telah diamanatkan oleh tujuan pendidikan nasional.
Kurikulum kita hanya dirancang untuk menghasilkan manusia-manusia yang pandai secara kognitif. Dalam masalah kurikulum pendidikan misalnya diarahkan kepada kurikulum yang memberikan bekal kepada peserta didik untuk mampu mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan pendapatan yang besar. Kurikulum tersebut dibuat sedemikian rupa dan untuk mengikutinya harus mengeluarkan uang sangat sangat besar. Jika dalam proses memperolehnya harus mengeluarkan dana yang besar, maka dapat dibayangkan setelah memperoleh pengetahuan tersebut. Peserta didik yang telah selesai akan menggunakan pengetahuan tersebut paling untuk mengembalikan modal dan tentu berupaya untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya. Karena memang teori modern mengatakan bahwa pendidian adalah investasi di masa depan. Investasi dalam dunia ekonomi dipahami sebagai modal yang akan dipetik keuntungannya di waktu yang akan datang. Sedangkan prinsip ekonomi yang diajarkan di sekolah menengah adalah keluarkan modal sedikit mungkin dan hasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Dari sini dapat dipahami bahwa kurikulum pendidikan telah dijadikan atau telah diselewengkan tujuannya hanya untuk mendapatkan pekerjaan. Sedangkan untuk menjadikan manusia yang utuh bukan hanya dimarjinalkan, akan tetapi memang dimatikan karena prinsip ekonomi tidak mengenal nilai-nilai spiritual, moralitas, kebersamaan. Tatanan kehidupan yang semrawut merupakan akibat dari system kebangsaan yang rapuh. Hal ini mengantarkan masyarakat Indonesia pada krisis yang berkepanjangan yang seakan tiada pernah berakhir. Berbagai peristiwa dan kejadian yang tidak menyenangkan selalu menghiasi kolom-kolom koran dan layar kaca kita hampir setiap hari, baik itu berupa berita eksploitasi pusat atas daerah, eksploitasi manusia atas manusia, penggunaan jabatan yang sewenang-wenang jauh dari sumpah jabatan, perilaku kekerasan di kalangan remaja, percaturan bisnis yang tidak beretika, perilaku poilitik yang culas serta kerusuhan-kerusuhan di berbagai daerah.Dalam aspek pendidik misalnya banyak sekali praktek dan perilaku penididik yang menjual nilai untuk mendapatkan uang. Bahkan ada sebagian pendidik yang menjadikan kewenangannya untuk memberikan nilai kepada peserta didik demi mendapatkan pendapatan dari peserta didiknya sendiri. Modusnya adalah dengan memberikan nilai rendah pada program regular, kemudian akan diberikan nilai agak tinggi atau bahkan tinggi pada program khusus dimana peserta didik juga membayar dengan biaya khusus. Praktik dan modus operasi yang demikian ini bukan hanya menjadi realitas, akan tetapi sudah menjadi penyakit kronis dalam dunia pendidikan, bahkan pendidikan Islam sendiri.
Adalah wajar bila muncul sebuah pertanyaan pada diri kita “pasti ada sesuatu yang salah dengan bangsa ini?’. Mengurai “sesuatu yang salah” ini bukanlah pekerjaan yang mudah, bahkan lebih sulit daripada mengurai benang yang paling kusut sekalipun. Menurut hemat saya kesemrawutan bangsa ini merupakan akumulasi dari akibat “sesuatu” yang salah tersebut. Kesemrawutan ini tidaklah cukup dijelaskan dengan hanya menggunakan hukum kausalitas sederhana. Fakta menunjukkan koruptor kelas kakap sebagian besar adalah orang yang berpendidikan tinggi bahkan orang yang mempunyai pengetahuan yang baik mengenai hukum. Orang yang suka membunuh saudaranya mengaku orang yang taat beragama. Seolah-olah menyalahkan kurangnya pendidikan dan pengetahuan agama masyarakat tidak berdasar. (Kadang kala saya berpikir terminology Hume bisa jadi benar ketika ia mengatakan tidak ada rasionalisasinya hukum kausalitas alam. Karena segala sesuatu kejadian di alam itu tidak hanya dipengaruhi oleh beberapa factor
tapi supra multi factor yang tidak akan pernah diketahui alasannya oleh manusia). Namun hati kecil saya percaya bahwa tidak ada sebab tanpa ada penyebab, tidak ada asap kalau tidak api demikian pepatah bijak mengatakan.
Nilai Moralitas dalam Sistem PendidikanKalau kita mencoba mau sedikit mengernyitkan dahi untuk menelusuri akar masalah penyebab krisis kebangsaan ini mungkin kita akan sampai pada salah satu titik simpul yang mempunyai andil besar dalam menyumbang kesemrawutan ini yaitu system pendidikan. Adalah benar adanya jika banyak ahli mengatakan bahwa institusi yang pertama kali harus bertanggungjawab terhadap krisis kebangsaan ini adalah dunia pendidikan, karena dunia pendidikan merupakan ujung tombak dalam membentuk karakter anak bangsa, karena dunia pendidikan yang memberikan warna hitam atau putih anak-anak bangsa. Pertanyaan selanjutnya apa yang salah dengan pendidikan kita sehingga menghasilkan luaran-luaran yang pintar dan cerdas secara kognitif tetapi miskin etika dan moral.Kalau kita berbicara tentang sistem pendidikan, secara sederhana dapat dilustrasikan seperti kerja sebuah pabrik dalam menghasilkan sebuah produk. Kerja sebuah pabrik selalu berurusan dengan tiga komponen, yaitu input, proses, produk. Input merupakan berbagai hal (sumber daya) yang digunakan dalam proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jika pabrik tersebut adalah pabrik mebel maka input tersebut bisa berupa kayu. Proses, adalah upaya untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, jadi pada bagian ini input tadi akan dibentuk sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Masih dengan menggunakan contoh pabrik mebel, maka bagian proses ini adalah kegiatan mengubah kayu menjadi sebuah mebel (sebagai tujuan yang telah ditetapkan). Luaran, merupakan hasil akhir dari kegiatan proses. Hasil akhir dari proses pada contoh pabrik di atas berupa mebel bisa kursi, meja, almari, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Cara kerja sistem pendidikan kurang lebih sama dengan sistem kerja sebuah pabrik yang telah diuraikan sebelumnya. Kalau kita hendak mengurai apa yang salah dengan system pendidikan kita, kita harus menelusuri komponen-komponen ini. Untuk mengurai apa yang salah dengan system pendidikan kita mari kita tinjau dulu tujuan pendidikan nasional kita yaitu ‘mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab. Namun agaknya tujuan pendidikan nasional ini untuk konteks sekarang harus diakui masih ’jauh panggang dari api’. Bila kita ibaratkan (masih dengan menggunakan contoh pabrik mebel) tujuannya hendak membuat mebel, produk yang dihasilkan malah ‘mobil-mobilan’ dari kayu. (masih mendingan jika hasilnya masih berupa mebel dengan mutu jelek. Praktik yang demikian akan menjadi hilang ketika nilai-nilai moralitas benar-benar terpancar dalam sistem pendidikan. Nilai-nilai moralitas yang diberikan kepada peserta didik selama ini hanyalah teori-teori yang tidak pernah dibuktikan dalam praktik kehidupan. Meskipun itu dalam praktik pendidikan itu sendiri. Praktik pelanggaran moralitas tinggi justru sudah diajarkan oleh para pendidik kepada peserta didik dengan berbagai praktik dan modus operandi dalam proses pengajaran dan ujian, salah satunya
adalah modus di atas. Aspek peserta didik merupakan korban dari sistem dan proses pendidikan yang ada.
Jika sistem pendidikan nasional maupun pendidikan Islam telah mengalami reduksi makna dari pendidikan menjadi sekedar penyampaian pengetahuan (transfer of knowledges), maka pada saat itulah peserta didik telah diberi pelajaran yang sangat luar biasa pengaruhnya dalam kehidupannya kelak. Peserta didik yang sudah berpengalaman, misalnya mahasiswa S1 atau S2 dan bahkan S3 yang telah memahami praktik-praktik demikian ini dan tidak mau memperhatikan nilai-nilai moralitas akan melakukan praktik-praktik asal bisa lulus dan selesai. Bahkan ada yang lebih tragis lagi yaitu asal dapat gelar, sehingga muncul pasar gelar di Indonesia yang beberapa tahun sebelum ini sangat marak dijajakan baik lewat media massa maupun media elektronik. Jual beli nilai, jual beli gelar, dan jual beli karya ilmiah adalah satu hal yang menunjukkan betapa rendah mental dan moralitas para peserta didik. Fenomena di atas merupakan realitas yang terjadi dalam dunia pendidikan yang ideologinya telah mengarah kepada ideologi materiliasme-kapitalis.
Bila kita mendapatkan luaran yang tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan akal sehat kita pasti mengira ada sesuatu yang tidak benar pada sisi input dan proses tersebut. Kalau kita berbicara Input dalam pendidikan paling tidak ada 3 faktor yang terlibat, 1) orang yang terlibat dalam proses, dalam hal ini siswa, guru, dan karyawan, 2) material, meliputi fasilitas, peralatan dan barang-barang yang diperlukan dalam proses, 3) tekhnologi, adalah tekhnik yang digunakan dalam proses untuk melaksanakan tugas-tugas praktis untuk mencapai tujuan. Sekarang mari kita coba melihat apa yang salah dari sisi input. Pertama kita tinjau dari sisi orang yang terlibat, siswa merupakan ’bahan mentah’ yang akan dibentuk oleh proses pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkan, dari sisi siswa merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, jadi pada sisi siswa kita harus berasumsi tidak ada masalah berarti. Selanjutnya adalah guru, faktor guru masih banyak menyisakan masalah terutama masalah pemerataan dan mutu guru, untuk mengatasi permasalahan mutu guru pemerintah sedang mensertifikasi ratusan ribu guru di Indonesia, permasalahan mutu guru ini merupakan kegagalan LPTK dalam menyiapkan guru berkualitas (menurut hemat saya, sertifikasi guru barangkali merupakan langkah yang tepat untuk jangka pendek, tetapi akan menjadi pemborosan besar-besaran bila tidak diiringi perbaikan kualitas institusi penghasil guru (LPTK), kegiatan sertifikasi guru merupakan indikator kegagalan LPTK dalam menghasilkan guru yang berkualitas). Faktor kedua berupa material seperti fasilitas, peralatan dan barang-barang yang diperlukan dalam proses, bila kita tinjau dari sisi ini, sudah menjadi rahasia umum bahwa fasilitas, peralatan dan barang-barang yang diperlukan dalam proses untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sungguh sangat memprihatinkan. Faktor ketiga teknologi, tekhnologi dalam konteks ini adalah tekhnologi yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan, menurut hemat saya sampai saat ini pemerintah masih ’kebingungan’ mencari ’tekhnologi’ yang cepat, tepat dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.
Materialisasi aspek manajemen pendidikan dapat dilihat pada praktik munculnya kebanggaan semua pihak baik pengelola, pendidik, peserta didik, dan wali akan megahnya gedung dan kampus dimana mereka berada dan ikut andil di dalamnya. Kemegahan gedung kampus dan sekolah menjadi tolok ukur majunya sebuah lembaga pendidikan. Jika orientasi kemegahan gedung kampus dan sekolah menjadi ukuran kemajuan sebuah pendidikan, maka dapat dibayangkan orientasi pendidikannya. Orientasi manajemen pendidikannya adalah pada kemegahan gedung secara fisikli, sementara kemegahan spsirtual dan moral;bisa termarjinalkan atau bahkan sama sekali ditiadakan. Semua pihak yang ada di dalamnya akan merasa bangga dan menganggap orang lain yang tidak berada di situ sebagai masyarakat pendidikan kelas rendah.
Manajemen pendidikan yang hanya mengarah pada kemegahan gedung kampus pada gilirannya akan ditundukkan atau dikalahkan oleh insitusi pendidikan lainnya yang memiliki modal yang luar biasa besarnya. Jadi pada dasarnya lembaga pendidikan atau dengan kata lain manajemen pendidikannya dimaksudkjan untuk berkompetisi. Dan kompetisi inilah yang menjadi darah dan energi bagi penyelenggaraan pendidikannya. Keberhasilan sebuah lembaga pendidikan hanya diukur dengan megahnya gedung, mahalnya SPP, banyaknya peminat, dan alumninya banyak yang menduduki jabatan tinggi. Inilah manajemen pendidikan di Indonesia saat ini.
Selanjutnya kita mencoba mengurai permasalah sistem pendidikan kita dari sisi proses. Bila kita mencoba mengidentifikasi komponen-komponen apa saja yang terlibat dari sisi proses paling tidak ada dua faktor penting yang sangat mempengaruhi output dari sistem pendidikan, yang pertama kurikulum dan yang kedua adalah proses pembelajaran. Kurikulum ini merupakan ’softwere’ yang paling vital dalam menghasilkan sebuah luaran, karena di dalam kurikulum ini sesungguhnya ’blue print’ sebuah luaran. Menurut hemat saya kurikulum pendidikan kita sebenarnya memang ’belum’ dirancang untuk menghasilkan produk luaran seperti telah diamanatkan oleh tujuan pendidikan nasional kita. Kurikulum kita sebenarnya dirancang untuk menghasilkan manusia-manusia yang pandai secara kognitif saja. Untuk membuktikan statment ini sebenarnya cukup mudah, mari kita tinjau kurikulum pendidikan dasar dan menengah kita, berapa banyak mata palajaran yang mampu mengajari siswa kita berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab?, berapa jam mata pelajaran agama untuk mengajari menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa?. Faktor kedua yang sangat berpengaruh adalah proses pembelajaran, harus kita akui proses pembelajaran kita masih terorientasi pada kegiatan menghafal, siswa tidak pernah diajarkan kemampuan berpikir (berpikir tinggi,`kreatif, kritis, apalagi ketrampilan sosial), siswa kita tidak ada bedanya dengan burung beo (saya masih ingat ketika saya masih menjadi guru GTT di SMA swasta di Malang, saya iseng-iseng bertanya pada siswa saya ’coba berikan contoh simbiosis mutualisme?’ hampir sebagian siswa saya menjawab burung jalak sama kerbau, ketika saya minta mereka memberi contoh lain semua siswa tidak bisa, dan pertanyaan ini saya ulang pada siswa yang baru masuk disekolah tersebut pada tahun berikutnya, dan jawaban mereka sama dengan jawaban siswa saya sebelumnya)
Materialisasi pada aspek lingkungan pendidikan merupakan fenomena yang sangat jelas. Lingkungan pendidikan di sini dipahami sebagai masyarakat yang berada di sekitar pendidikan atau dengan kata lain adalah masyarakat Indonesia sendiri. Masyarakat Indonesia sejak memasuki era modernisasi telah mengalami pergeseran yang luar biasa. Pergeseran tersebut mencakup pergeseran orientasi kehidupan, pergeseran budaya, pergeseran gaya hidup, pergeseran pandangan hidup, pergeseran pertilaku politik, pergeseran perilaku ekonomi, dan pergeseran terhadap ajaran agama. Pergeseran-pergeseran tersebut jmuarany adalah disebabkan oleh adanya modernisasi yang terus "dibombardirkan" kepada masyarakat, baik melalui jalur pendidikan, jalur media massa, dan jalur birokrasi. Modernisasi pada intinya adalah upaya rasionalisasi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dari yang pada mulanya kental akan nuansa religius, nuansa sakralitas, dan nuansa spiritual bahkan nuansa transendental menjadi tidak bernuansa sama sekali kecuali nuansa rasionalitas, nuansa obyektivitas, dan nuansa realitas-empiris. Massyarakat yang telah bergeser pandangan hidupnya menjadi sebagaimana dikemukakan di atas, maka menjadikan danmenganggap pendidikan sebasgai investasi dan ketika selesai akan mendapatkan keuntungan lebih besar adalah sangat wajar. Semua ini pada dasarnya adalah materialsasi lingkungan pendidikan di Indonesia, termasuk pendidikan Islam. Materialisasi tujuan pendidikan merupakan landasan awal bagi proses materialisasi seluruh aspek di atas. Tujuan di manapun dia berada merupakan muara akhir dari semua proses yang ada sebelumnya, termasuk di sini adalah dslam proses pendidikan. Tujuan pendidikan yang dimaterialisasikan adalah upaya mencapai tujuan pendidikan nasioanl maupun pendidikan Islam dengan asumsi dapat diukur secara kuantitatif dan dapat diliuhat jhasilnya secara nyata. Tujuan-tujuan pendidikan yang telah mengalami materialisasi dapat dilihat pada tujuan para pendidik. Misalnya, berapa alumni yang telah menjadi dokter, berapa yang telah menjadi pengacara, berapa yang telah menjadi pejabat tinggi, berapa alumni yang telah menjadi dewan. Dengan melihat jumlah alumni yang telah menduduki jabatan apapun akan dapat diprediksikan penghasilan mereka. Setelah diketahui pendapatan par alumni, maka dapat diketahui keberhasilan sebuah lemabaga pendidikan. Sangat jarang atau bahkan tidak ada berapa alumni yang telah menjadi manusia bermoral, berapa alumni yang telah membuka kesadaran masyarakat akan arti pentingnya persaudaraan, berapa alumni yang telah mampu memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat tanpa pamrih apapun, berapa alumni yang telah benar-benar melaksanakan tujuan pendidkannya yaitu menjadi manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya di sini berarti secara jasmani dan ruhani, secara material dan spiritual, dan secara fisik dan mental, serta secara intelektual dan moral telah terjadi keseimbangan yang nyata. Jarang sekali atau bahkan tidak ada sensus keberhasilan pendidikan yang mengukur kesuksesannya dengan ranah yang demikian ini. (Wallohu A’lam Bishawab)
KepustakaanCahyana, Ade, Indonesia 2010: Merubah Mitos menjadi Realitas Pembangunan, From:
http://www.depdiknas.go.id/Jurnal/26/indonesia 2010 Ade Cahyana.htm, sabtu, 16/9/ 2006, jam. 13.10.
Freire, Paulo, 1995, Pendidikan Kaum Tertindas, Terjemahan, Utomo Dananjaya, LP3ES, Jakarta.
Kelompok Kerja Pengkajian dan Perumusan, Rangkuman Filosofi, Kebijaksanaan dan Strategi Pendidikan Nasional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1999, Jakarta.
Mastuhu, 2003, Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21, Safiria Insania Press dan MSI, Yogyakarta.
Musa, Ibrahim, Otonomi Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah, From: http://202.159.18.43/jp/22ibrahim.htm, Akses, 5 Juni 2002
Nomida Musnir, Diana, 2000, Arah Pendidikan Nasional dalam Perspektif Historis, dalam Buku: Sindhunata [editor], 2000, Menggagas Paradigma Baru Pendidikan, Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi, Kanisius, Yogyakarta.
Purbo, Onno W., Pergeseran Drastis Paradigma Dunia Pendidikan, From: http://bebas.vlsm.org/v09/onno-ind-1/application/education/pergeseran-drastis-paradigma-dunia-pendidikan-1998.rtf, 7/11/2003.
Sanaky, Hujair AH., 2003, Paradigma Pendidikan Islam, Membangun Masyarakat Madani Indonesia, Safiria Insania dan MSI, Yogyakarta.
--------, 2005, Sertifikasi dan Profesionalisme Guru di Era Reformasi Pendidikan, Jurnal Pendidikan Islam [JPI], Volume XII TH VIII Juni 2005, ISSN: 0853-7437, Jurusan Tarbiyah Fakultas Ilmu Agama UII, Yogyakarta.
----------, Paradigma Pembangunan Pendidikan di Indonesia Pasca Reformasi Antara Mitos dan Realitas.
Suryadi, Ace, Pengelolaan Pendidikan Perlu Paradigma Baru, From:http://www. Kompas.com/kompas-cetak/0010/16/DIKBUD/peng09.htm.,akses, Sabtu, 23/8/ 2003.
Suyanto & Djihad Hisyam, 2000, Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III, Adicita Karya Nusa, Yogyakarta.
Suyanto, 2006, Dinamika Pendidikan Nasional [Dalam Percaturan Dunia Global], PSAP Muhammadiyah, Jakarta.
Soedjiarto, 1999. "Memahami Arahan Kebijakan GBHN 1999-2004 tentang Pendidikan Sebagai Upaya Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan Membangun Peradaban Negara bangsa Indonesia", Makalah, Primagama-IPSI-PGRI, Yogyakarta.
Tilaar, H.A.R., 1998, Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Abad 21, Tera Indonesia, Magelang.
Yacub, Muhammad, From: http://www.depdiknas.go.id/Jurnal/27/suatu opini mengenai reformasi_s.htm, akses, Rabu,20/9/2006, jam.13.35.
Zamroni, 2000, Paradigma Pendidikan Masa Depan, Adipura, Yogyakarta.Insentif bagi Industri yang Lakukan Pelatihan, Kompas, Kamis, 26 Juni 1997
Tempo, 7 Januari 2001Lewat Persentase Anggaran, Belajar dari Negara Lain, Kompas, Sabtu, 2 Mei 1998Kabupaten dan Kota Menjadi Basis Pengelolaan Pendidikan Dasar, Kompas, Rabu, 24
Februari 1999Sekolah Plus, Menghitung Dengan Dollar, Suplemen, Tempo, 18 Maret 2001Kasrai, Reza, Corporate University, CFS-Quebec Education Action, edisi musim gugur
2001. http://www.newyouth.com/archives/campaigns/mexico/UNAM.aspRUU BHP, Skenario Neoliberalisme, SUARA PEMBARUAN DAILY, September 5,
2007
BHMN, Neoliberalisme Pendidikan, Suara Pembaruan March 15, 2007Muhammad Roqib, M.Ag , Politik Pendidikan dan Pendidikan Politik Sebagai Upaya
Memajukan Bangsa, Jumat, 2008 Agustus 08Pan Mohamad Faiz (New Delhi) , Polemik Inkonstitusionalitas Anggaran Pendidikan,
Dimuat pada H.U. Seputar Indonesia (05/05/07)Pan Mohamad Faiz , Menanti Political Will Pemerintah di Sektor Pendidikan, Pikiran
Rakyat Bandung , October 05, 2006Abu Khaulah Zainal Abidin , “Ideologi Pendidikan Kita” Maret 22, 2008, Posted by
rumahbelajaribnuabbas in Pendidikan. Greg Russell, Bentuk Pemerintahan Berdasarkan Konstitusi (terj.), Demokrasi, Office of
International Information Programs, US. Dept. of States., tanpa tahun.Richard C.Schroeder, Garis Besar Pemerintahan Amerika Serikat (terj.), Office of
International Information Programs – United States Dept. of States, 2000.The center on Education Policy, Washington D.C., The Federal Role in US Education,
US Society and Values, e-journals of the U.S.. Department of State, vol 5 no. 2, June 2000.
Tiffany Danitz, The Standards Revolution In U.S. Schools, US Society and Values, e-journals of the U.S.. Department of State, vol 5 no. 2, June 2000.
Anonim, The Federal Role in Education - Overview , US Department of Education in http://www.ed.gov
Anonim, College Rankings, America’s "Top" Schools, US Society and Values, e-journals of the U.S.. Department of State, , vol 10 no. 2, November 2005.
Judith S. Eaton, An Overview of U.S. Accreditation, publication of Council for Higher Education Accreditation, tanpa tahun .
Robert H. Bruininks, Public Universities In The United States, US Society and Values, e-journals of the U.S.. Department of State, , vol 10 no. 2, November 2005.
James W. Wagner, What Is A Large, Private Research University?, US Society and Values, e-journals of the U.S.. Department of State, , vol 10 no. 2, November 2005.
Anonim, The Cost Of College In The United States, US Society and Values, e-journals of the U.S.. Department of State, , vol 10 no. 2, November 2005.
Martina Schulze, Possible Sources Of Financial Aid, US Society and Values, e-journals of the U.S.. Department of State, , vol 10 no. 2, November 2005.
Margaret S. Branson, At The Core Of U.S. Education, A Passion For Learning, US Society and Values, e-journals of the U.S.. Department of State, vol 5 no. 2, June 2000.
Hizbut Tahrir, How the Khilafah was Destroyed, Khilafah Publication, London 2000Ideologi Pendidikan Sebuah Pengantar , Tuesday, March 18, 2008
http://www.fppm.org/Info%20Anda/pendidikan%20yang%20membebaskan.htm.Mansour Faqih dan Toto Rahardjo. Pendidikan yang membebaskan, 09 Agustus 2002
http://www.pikiran-rakyat.com/Artikel/0802.htm. Ahmad Dahidi & Miftachul Amri. Potret Pendidikan di Jepang, Sebuah Refleksi. 22 Mei
2003.Agus Syafii <agussyafii@yaho...>, Problem Pendidikan di Era Reformasi, February 18,
2008
Kepentingan Politik Masih Terlihat Lebih Menonjol, http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0708/08/humaniora/3750060.htm
Pendidikan Indonesia Alami Proses Involusi, Harian Kompas, 4 September 2004Agung Pramanto (JIP'98)/Redaksi AP, Dilema Otonomi Pendidikan: Catatan Dari
Seminar Otonomi Pendidikan Nasional 2001 SMFSUI Otonomi Pendidikan Masih Hadapi Banyak Kendala, Jakarta, Sinar Harapan, 2003St Kartono , Memahami Otonomi Pendidikan beserta Implikasinya, SUARA
PEMBARUAN DAILY , 2002Uni Eropa: Perdamaian Aceh Bukti Kekuatan Soft Power, TEMPO Interaktif, Jakarta,
Rabu, 13 Desember 2006 | 21:15 WIB"Soft Power" dan Jejak Bush , Kompas, 21 Nopember 2006Muhammad Roqib, M.Ag, Politik Pendidikan dan Pendidikan Politik Sebagai Upaya
memajukan Bangsa, http://roqibstain.blogspot.com/2008/08/politik-pendidikan-dan-pendidikan.html
Marsudi Budi Utomo, 50 Tahun RI-Jepang, December 24, 2007Novian Widiadharma, UIN Yogyakarta , Art, Soft Power, dan Tata Dunia Baru,
Wednesday, 13 August 2008 07:15 Nurani Soyomukti (Esai Politik): "Soft Power", Strategi Gerakan Anti Teror(Isme),
Sabtu, 2007 Agustus 25Dino Patti Djalal Juru Bicara Kepresidenan, SBY dan "Soft Power" , URL Source:
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0506/13/opini/1806887.htmMegawati: Pandangan Tentang Pendidikan Murah dan Gratis, Menyesatkan, Rabu, 05
Mei 2004Khoirul Anwar , Membangun Moral di abad Global , 15 Juni 2008 - 17:05 Iskandar Alisjahbana , Cyberspace dari Peradaban Gelombang-Ketiga "Sifat dan Hakekat
Manusia & Masyarakat di Dalam Era-Informasi" , Edisi ke Tujuh, April 1997Baridul Islam Pr, “Abuse of Power” Kaum Intelektual, Purwokerto, 16 Maret 2003Anonym, Masalah Pendidikan Di Indonesia, August 29, 2007 Yusufhadi Miarso, Pengembangan Terkini Sistem Pendidikan dan Pembelajaran di
Perguruan Tinggi, Disampaikan dalam Semiloka Pengajaran dan Program Magang, Departemen Ilmu Hubungan Internasional, FISIP-UI, 2 Mei 2008
Banathy, Bela H. (1991). Systems Design of Education. A journey to create the future. Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology Publications
Dabbagh, Nada & Brenda Bannan-Ritland. Online Learning. Concept, strategies and application. Columbus,OH : Pearson. 2005
Miarso, Yusufhadi. (2005). Menyemai Benih Teknologi Pendidikan. Jakarta: Pustekkom-Kencana
Reigeluth, Charles M. and Robert J. Garfinkle. (eds.)(1994). Systemic Change in Education. Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology Publications
Toffler, Alvin. The Third Wave. London : Pan Books Ltd.UNSCTD. Knowledge Society. Published for and on behalf of The Unted Nations.
Oxford,NY : Oxford University Press. 1998 Tim MWA Wakil Mahasiswa KM ITB dan Kastrat Kabinet KM ITB, Positioning Paper.
Pernyataan Sikap KM ITB terhadap RUU BHP BHP: Gaya Baru Otokrasi Pendidikan Indonesia
NIM. Sistem Pendidikan Yang Berkarakter dan Berbudaya, February 28, 2007
Benedict Richard O'Gorman Anderson. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Edition: 2, revised. Verso, 1991
Bertrand Russell. Power: A New Social Analysis. Edition: 2. W.W.Norton & company, 1938
Chantal Mouffe . Gramsci and Marxist Theory: essays. Routledge, 1979Dewey, John, 1974, The Child and The Curriculum,and The School and Society, Chicago
and London, The University of Chicago Press. Giddens, Anthony, The Nation States and Violence: Volume Two of a Contemporary
Immanuel Maurice Wallerstein, Immanuel Wallerstein. The Modern World-system II. Edition: 2. Academic Press, 1980
Masinambow, EKM (ed), 1997, Koentjaraningrat dan Antropologi Indonesia, Jakarta, AAI dan Yayasan Obor Indonesia.
McQuail, Denis, 2000, Mass Communication Theories, Fourth edition, Sage Publication, London
Michael Wallerstein : The Political Economy of Inequality, Unions, amd Social Democracy. New York: Cambridge University Press, 2008
Renate Holub. Antonio Gramsci: Beyond Marxism and Postmodernism. Routledge, 1992Rudolf Ekstein, Robert S. Wallerstein. The Teaching and Learning of Psychotherapy.
Edition: 2. Basic Books, 1958Siswanta, Relasi kekuasaan: telaah pemikiran Antonio Gramsci dalam konteks politik
Indonesia kontemporer. Media Wacana, 2006Sutaarga, Moh. Amir. 1997/1998. Pedoman Penyelenggaraan dan Pengelolaan Museum.
Jakarta: Proyek Pembangunan Permuseuman JakartaVedi R. Hadiz, Benedict Richard O'Gorman Anderson. Politik, budaya, dan perubahan
sosial: Ben Anderson dalam studi politik Indonesia. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama bekerja sama dengan Yayasan SPES, 1992
FX Sugiyanto, Ilusi Kurikulum Pendidikan dalam Kuasa Neoliberalisme , Saturday, 02 August 2008