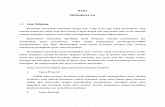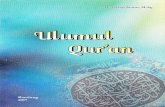Makalah Laporan Sgd Kep
-
Upload
regina-masli-putri -
Category
Documents
-
view
97 -
download
6
Transcript of Makalah Laporan Sgd Kep

MAKALAH LAPORAN SGD
MALNUTRISI (KURANG ENERGI PROTEIN)
Diajukan untuk memenuhi nilai matakuliah Sistem Digestif I pada semester genap
DISUSUN OLEH :
TUTOR 10
Ani Rosmardiani (220110110106)
Asti Aprilianti (220110110027)
Regina Masli P (scriber 2) (220110110039)
Euis Fitriana Dewi (scriber 1) (220110110029)
Evie Pratiwi (220110110017)
Karina Delistia D (220110110137)
Neng Tuti H (220110110067)
Nurnila Novi A (220110110031)
Rahma Putri N. (220110110076)
Rati Erviani (chair) (220110110001)
Rully Andari A (220110110136)
Siti Rahmiati P. (220110110069)
Yulia Latifah (220110110147)
FAKULTAS KEPERAWATANUNIVERSITAS PADJADJARAN
2013

KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kerena penulis dapat menyelesaikan penyusunan makalah
ini. Makalah ini merupakan hasil dari reporting kelompok 10 yang berjudul “MALNUTRISI
(KURANG ENERGI PROTEIN)” disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Digestif I.
Dalam penyusunan makalah ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada :
1. Pak Afif selaku dosen tutor mata kuliah Sistem Digestif I yang memberikan
pengajaringanan kepada penulis;
2. Siti Yuyun selaku dosen coordinator mata kuliah Sistem Digestif I;
3. Orang tua kami tercinta yang selalu memberikan doa restu dan dukungan dalam proses
pembelajaringanan kami di Fakultas Keperawatan;
4. Teman-teman Tutor 10 yang telah membantu dan ikut berpartisipasi dalam penyelesaian
makalah laporan SGD ini.
Penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi perbaikan di hari
kemudian.
Akhir kata, penulis berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat dalam proses
pembelajaringanan di Fakultas Keperawatan.
Jatinangor, Maret 2013
Penulis

BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Banyaknya angka penderita malnutrisi, tidak hanya di Indonesia, tapi diseluruh dunia
terutama di negara-negara berkembang dengan sisi ekonomi yang rendah, sehingga
kebutuhan hidup tidak terpenuhi dengan baik. Malnutrisi banyak diderita pada anak-anak
balita, bisa dikarenakan pengetahuan orang tua akan penenuhan gizi untuk anaknya yang
sedang tumbuh dan berkembang sehingga membutuhkan asupan gizi yang cukup. Tidak
hanya itu, sudah disinggung mengenai masalah ekonomi, yang selalu menjadi alasan utama
pemenuhan gizi anak terhambat dan tidak tercukupi.
Berdasarkan hal tersebut, perlunya pengetahuan lengkap akan malnutrisi pada anak
khususnya pada anak dengan kurang energy protei yang biasa disebut KEP. KEP itu sendiri
terdiri dari KEP ringan, sedang dan berat. KEP berat adalah yang paling sering ditemukan
terutama marasmus, kemudian kwashiorkor dan marasmus kwashiorkor.
KEP ini terjadi dalam jangka waktu lama yang dibiarkan terus menerus dalam
keadaaan kurang gizi. Anak yang kurang gizi akan menurun daya tahan tubuhnya, sehingga
mudah terkena penyakit infeksi, sebaliknya anak yang menderita penyakit infeksi akan
mengalami gangguan nafsu makan dan penyerapan zat-zat gizi sehingga menyebabkan
kurang gizi dan ini dapat menyebabkan ganggguan tumbuh kembang yang akan
mempengaruhi tingkat kesehatan, kecerdasan dan produktivitas di masa dewasa.
2. Tujuan Penulisan
Penulisan makalah ini dilakukan untuk memenuhi tujuan-tujuan yang diharapkan
dapat bermanfaat bagi kita semua dalam menambah ilmu pengetahuan dan wawasan. Secara
terperinci tujuan dari penelitian dan penulisan makalah ini adalah :
- Mengetahui anatomi fisiologi sistem digestif yang mendasari kasus malnutrisi (kurang
energy protein).
- Mengetahui pengertian dari malnutrisi (kurang energy protein).
- Mengetahui faktor penyebab terjadinya malnutrisi (kurang energy protein)
- Mengetahui perjalanan timbulnya malnutrisi (kurang energy protein)

- Mengetahui asuhan keperawatan pada malnutrisi (kurang energy protein)
- Menganalisa kasus tentang malnutrisi (kurang energy protein) dan pemberian intervensi
yang harus diberikan

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
1. ANATOMI FISIOLOGI SISTEM DIGESTIF
Saluran pencernaan makanan merupakan saluran yang menerima makanan dari
luar dan mempersiapkannya untuk diserap oleh tubuh dengan jalan proses pencernaan
(pengunyahan, penelanan dan pencampuran) dengap enzim dan zat cair yang terbentang
mulai dari mulut (oris) sampai anus.
Sistem pencernaan (bahasa Inggris: digestive system) adalah sistem organ dalam
hewan multisel yang menerima makanan, mencernanya menjadi energi dan nutrien, serta
mengeluarkan sisa proses tersebut melalui dubur. Pada dasarnya sistem pencernaan
makanan dalam tubuh manusia terjadi di sepanjang saluran pencernaan (bahasa Inggris:
gastrointestinal tract) dan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu proses penghancuran makanan
yang terjadi dalam mulut hingga lambung.Selanjutnya adalah proses penyerapan sari -
sari makanan yang terjadi di dalam usus. Kemudian proses pengeluaran sisa - sisa
makanan melalui anus.
Sistem pencernaan (mulai dari mulut sampai anus) berfungsi sebagai berikut:
- Menerima makanan
- Memecah Makanan Menjadi Zat-Zat Gizi (Suatu Proses Yang Disebut Pencernaan)
- Menyerap Zat-Zat Gizi Ke Dalam Aliran Darah
- Membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna dari tubuh.
Saluran pencernaan terdiri dari mulut, tenggorokan, kerongkongan, lambung, usus halus, usus
besar, rektum dan anus.
Sistem pencernaan juga meliputi organ-organ yang terletak diluar saluran pencernaan, yaitu
pankreas, hati dan kandung empedu.

MULUT, TENGGOROKAN & KERONGKONGAN
Mulut merupakan jalan masuk untuk sistem pencernaan dan sistem pernafasan. Bagian dalam
dari mulut dilapisi oleh selaput lendir. Saluran dari kelenjar liur di pipi, dibawah lidah dan
dibawah rahang mengalirkan isinya ke dalam mulut. Di dasar mulut terdapat lidah, yang
berfungsi untuk merasakan dan mencampur makanan. Di belakang dan dibawah mulut terdapat
tenggorokan (faring).
Pengecapan dirasakan oleh organ perasa yang terdapat di permukaan lidah. Penciuman dirasakan
oleh saraf olfaktorius di hidung. Pengecapan relatif sederhana, terdiri dari manis, asam, asin dan
pahit. Penciuman lebih rumit, terdiri dari berbagai macam bau.
Makanan dipotong-potong oleh gigi depan (incisivus) dan dikunyah oleh gigi belakang (molar,
geraham), menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dicerna. Ludah dari kelenjar ludah
akan membungkus bagian-bagian dari makanan tersebut dengan enzim-enzim pencernaan dan
mulai mencernanya. Pada saat makan, aliran dari ludah membersihkan bakteri yang bisa

menyebabkan pembusukan gigi dan kelainan lainnya. Ludah juga mengandung antibodi dan
enzim (misalnya lisozim), yang memecah protein dan menyerang bakteri secara langsung.
Proses menelan dimulai secara sadar dan berlanjut secara otomatis. Epiglotis akan tertutup agar
makanan tidak masuk ke dalam pipa udara (trakea) dan ke paru-paru, sedangkan bagian atap
mulut sebelah belakang (palatum mole, langit-langit lunak) terangkat agar makanan tidak masuk
ke dalam hidung.
Kerongkongan (esofagus) merupakan saluran berotot yang berdinding tipis dan dilapisi oleh
selaput lendir. Kerongkongan menghubungkan tenggorokan dengan lambung. Makanan didorong
melalui kerongkongan bukan oleh gaya tarik bumi, tetapi oleh gelombang kontraksi dan relaksasi
otot ritmik yang disebut dengan peristaltik.
LAMBUNG
Lambung merupakan organ otot berongga yang besar dan berbentuk seperti kandang keledai,
terdiri dari 3 bagian yaitu kardia, fundus dan antrum.
Makanan masuk ke dalam lambung dari kerongkongan melalui otot berbentuk cincin (sfingter),
yang bisa membuka dan menutup. Dalam keadaan normal, sfingter menghalangi masuknya
kembali isi lambung ke dalam kerongkongan.
Lambung berfungsi sebagai gudang makanan, yang berkontraksi secara ritmik untuk mencampur
makanan dengan enzim-enzim.

USUS HALUS
Lambung melepaskan makanan ke dalam usus dua belas jari (duodenum), yang merupakan
bagian pertama dari usus halus.
Makanan masuk ke dalam duodenum melalui sfingter pilorus dalam jumlah yang bisa dicerna
oleh usus halus. Jika penuh, duodenum akan mengirimkan sinyal kepada lambung untuk berhenti
mengalirkan makanan. Duodenum menerima enzim pankreatik dari pankreas dan empedu dari
hati.
Cairan tersebut (yang masuk ke dalam duodenum melalui lubang yang disebut sfingter Oddi)
merupakan bagian yang penting dari proses pencernaan dan penyerapan.
Gerakan peristaltik juga membantu pencernaan dan penyerapan dengan cara mengaduk dan
mencampurnya dengan zat yang dihasilkan oleh usus.
Beberapa senti pertama dari lapisan duodenum adalah licin, tetapi sisanya memiliki lipatan-
lipatan, tonjolan-tonjolan kecil (vili) dan tonjolan yang lebih kecil (mikrovili).
Vili dan mikrovili menyebabkan bertambahnya permukaan dari lapisan duodenum, sehingga
menambah jumlah zat gizi yang diserap.

Sisa dari usus halus, yang terletak dibawah duodenum, terdiri dari jejunum dan ileum. Bagian ini
terutama bertanggungjawab atas penyerapan lemak dan zat gizi lainnya. Penyerapan ini
diperbesar oleh permukaannya yang luas karena terdiri dari lipatan-lipatan, vili dan mikrovili.
Dinding usus kaya akan pembuluh darah yang mengangkut zat-zat yang diserap ke hati melalui
vena porta. Dinding usus melepaskan lendir (yang melumasi isi usus) dan air (yang membantu
melarutkan pecahan-pecahan makanan yang dicerna). Dinding usus juga melepaskan sejumlah
kecil enzim yang mencerna protein, gula dan lemak. Kepadatan dari isi usus berubah secara
bertahap, seiring dengan perjalanannya melalui usus halus.
Di dalam duodenum, air dengan cepat dipompa ke dalam isi usus untuk melarutkan keasaman
lambung. Ketika melewati usus halus bagian bawah, isi usus menjadi lebih cair karena
mengandung air, lendir dan enzim-enzim pankreatik.
Absorpsi yang terjadi pada usus halus:
a) Absorpsi ion-ion
ü Transpor aktif natrium.
Tenaga penggerak absorpsi natrium disediakan oleh transport akrif natrium dari dalam sel epitel
melalui bagian basal dan sisi dinding sel masuk ke dalam ruang paraselular. Transport aktif ini
mengikuti hukum yang biasa beraku untuk transport aktif: proses ini memerlukan energy, dan
proses energy dikatalisis oleh enzin adenosine trifosfat yang sesuai didalam membrane sel.

Sebagian dari atrium diabsorpsi bersama dengan ion klorida; sebenarna ion klorida bermuatan
negatif terutama secara pasif “ditarik” oleh muatan listrik positif ion natrium.
Transpor aktif natrium melalui membran basolateral sel mengurangi konsentrasi natrium di
dalam sel mengurangi konsentrasi natrium di dalam sel sampai ke nilai yang rendah ( kira-kira
50 mEq/L). karena konsentrasi natrium dalam kimus normalnya kira-kira 142 mEq/L (yaitu,
hamper sebanding dengan konsentraasi natrium dalam plasma), natrium bergerak menuruni
gradient elektrokimia yang tinggi dari kimus melalui brush border sel epitel masuk kedalam
sitoplasma sel.hal ini memungkinkan lebih banyak ion natrium yang dapat ditranspor oleh sel
epitel masuk kedalam ruang paraselular.
ü Osmosis Air
Osmosis ini terjadi karena gradient osmotik yang besar telah dibentuk oleh peningkatan
konsentrasi ion dalam ruang paraselular. Sebagian besar osmosis ini terjadi melalui taut erat
diantara batas apical sel-sel apitel, tetapi banyak juga terjadi di sel itu sendiri; dan pergerakan
osmotic air menciptakan aliran air ke dalam dan melewati ruang paraselular dan akhirnya masuk
ke dalam sirkulasi darah vilus.
ü Aldosteron sangat meningkatkan absorpsi natrium
Fungsi aldosteron ini dalam saluran usus sama dengan efek yang di capai oleh aldosteron di
dalam tubulus ginjal. Yang juga bekerja untuk menahan natrium klorida dan air di dalam tubuh
saat seseorang mengalami dehidrasi.
ü Absorpsi ion klorida dalam duodenum dan yeyunum
Pada usus halus bagian atas, absorpsi ion klorida berlangsung cepat dan dan berlangsung
terutama melalui difusi yaitu, absorpsi ion natrium melalui epitel menciptakan
keelektronegatifan dalam kimus dan keelektropositifan pada ruang paraselular diantara sel epitel.
Kemudian ion klorida bergerak sepanjang gradient listrik ini “mengikuti” ion natrium.
ü Absorpsi ion bikarbonat dalam duodenum dan yeyunum
Ion bikarbonat diabsorpsi secara tidak langsung dengan cara berikut: bila ion natrium diabsorpsi,
ion hydrogen dalam jumlah sedang disekresi kedalam lumen usus untuk ditukar dengan beberapa

natrium. Ion hydrogen ini kemudian akan bergabung dengan ion bikarbona untuk membentuk
asam karbonat, yang kemudian berdisosiasi untuk membentuk air dan karbon dioksida.
b) Absorpsi Karbohidrat
Hampir sebagian karbohidrat dalam makanan diabsorpsi ke dalam bentuk monosakarida (glukosa
dan fruktosa) dan hanya sebagian kecil yang diabsorpsi sebagai disakarida (sukrosa, maltosa dan
galaktosa). Monosakarida yang paling banyak diabsorpsi adalah glukosa, biasanya mencapai
lebih dari 80% kalori karbohidrat yang diabsorpsi, karena glukosa merupakan produk pencernaan
akhir dari makanan karbohidrat yang paling sering dikonsumsi manusia, yaitu zat tepung. 20%
sisanya adalah monosakarida yang diabsorpsi hampir seluruhnya dari galaktosa dan fruktosa.
Galaktosa berasal dari susu dan fruktosa merupakan salah satu monosakarida yang dicerna dari
gula tebu.
c) Absorpsi Protein
Hasil dari pemecahan protein menjadi polipeptida oleh enzim tripsin dan kimotripsin yang
disekresikan pada pankreas kemudian dibawa ke tahap terakhir pencernaan protein di lumen
usus. Di lumen usus, protein dibawa ke enterosit yang melapisi vili usus halus, terutama di dalam
duodenum dan jejunum. Sel-sel ini memiliki suatu brush border yang mengandung beratus-ratus
mikrovili. Pada membran sel masing-masing mikrovili terdapat banyak peptidase yang menonjol
keluar melalui membran, tempat peptidase berkontak dengan cairan usus.
Dua jenis enzim peptidase yang sangat berperan penting adalahaminopolipeptidase dan beberapa
dipeptidase. Enzim-enzim tersebut bertugas memecahkan sisa polipeptida-polipeptida yang besar
menjadi bentuk tripeptida dan dipeptida, serta beberapa menjadi asam amino. Baik asam amino
ditambah peptida dan tripeptida dengan mudah ditranspor melalui membran mikrovili ke bagian
dalam enterosit.
Akhirnya di dalam sitosol enterosit terdapat banyak peptidase lain yang spesifik untuk jenis
ikatan antara asam amino yang masih tertinggal. Dalam beberapa menit, sebenarnya semua
dipeptida dan tripeptida yang masih tertinggal akan dicerna sampai tahap akhir untuk
membentuk asam amino tunggal, kemudian asam amino tunggal tersebut dihantarkan ke sisi lain
dari enterosit dan dari tempat itu ke dalam darah.

Lebih dari 99% produk pencernaan akhir protein yang diabsorpsi merupakan asam amino
tunggal, jarang berupa peptida, dan lebih jarang lagi berupa molekul protein utuh. Molekul
protein utuh yang sangat sedikit diabsorpsi ini kadang-kadang dapat menyebabkan gangguan
alergi yang berat atau gangguan imunologik.
d) Absorpsi Lemak
Ketika lemak dicerna untuk membentuk monogliserida dan asam lemak bebas, kedua produk
akhir pencernaan ini pertama-tama akan larut dalam gugus pusat lipid dari misel empedu. Karena
dimensi molekulnya, misel hanya berdiameter 3 sampai 6 nanometer, dan juga karena muatan
luarnya yang sangat tinggi, zat-zat ini dapat larut dalam kimus. Dalam bentuk ini, monogliserida
dan asam lemak bebas ditranspor kepermikaan mikrovilibrush border sel usus dan kemudian
menembus ke dalam ceruk di antara mikrovili yang bergolak dan bergerak. Di sini,ke duanya
baik monogliserida dan asam lemak segera berdifusi ke luar misel dan masuk kebagian dalam sel
epitel yang dapat terjadi karena lipid juga larut dalam membran sel epitel. Proses ini
meninggalkan misel empedu tetap di dalam kimus, yang selanjutnya akan melakukan fungsinya
berkali-kali untuk membantu mengabsorpsi lebih banyak monogliserida dan asam lemak lagi.
PANKREAS
Pankreas merupakan suatu organ yang terdiri dari 2 jaringan dasar:
- Asini, menghasilkan enzim-enzim pencernaan
- Pulau pankreas, menghasilkan hormon.
Pankreas melepaskan enzim pencernaan ke dalam duodenum dan melepaskan hormon ke dalam
darah. Enzim-enzim pencernaan dihasilkan oleh sel-sel asini dan mengalir melalui berbagai
saluran ke dalam duktus pankreatikus.
Duktus pankreatikus akan bergabung dengan saluran empedu pada sfingter Oddi, dimana
keduanya akan masuk ke dalam duodenum.
Enzim yang dilepaskan oleh pankreas akan mencerna protein, karbohidrat dan lemak. Enzim
proteolitik memecah protein ke dalam bentuk yang dapat digunakan oleh tubuh dan dilepaskan
dalam bentuk inaktif. Enzim ini hanya akan aktif jika telah mencapai saluran pencernaan.

Pankreas juga melepaskan sejumlah besar sodium bikarbonat, yang berfungsi melindungi
duodenum dengan cara menetralkan asam lambung.
3 hormon yang dihasilkan oleh pankreas adalah:
- Insulin, yang berfungsi menurunkan kadar gula dalam darah
- Glukagon, yang berfungsi menaikkan kadar gula dalam darah
- Somatostatin, yang berfungsi menghalangi pelepasan kedua hormon lainnya (insulin dan
glukagon).
HATI
Hati merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh, terletak dalam rongga perut sebelah
kanan,tepatnya di bawah diafragma. Berdasarkan fungsinya, hati juga termasuk sebagai alat
ekskresi. Hal ini dikarenakan hati membantu fungsi ginjal dengan cara memecah beberapa
senyawa yang bersifat racun dan menghasilkan amonia, urea, dan asam urat dengan
memanfaatkan nitrogen dari asam amino. Proses pemecahan senyawa racun oleh hati disebut
proses detoksifikasi.
Zat-zat gizi dari makanan diserap ke dalam dinding usus yang kaya akan pembuluh darah yang
kecil-kecil (kapiler).
Kapiler ini mengalirkan darah ke dalam vena yang bergabung dengan vena yang lebih besar dan
pada akhirnya masuk ke dalam hati sebagai vena porta. Vena porta terbagi menjadi pembuluh-
pembuluh kecil di dalam hati, dimana darah yang masuk diolah.
Darah diolah dalam 2 cara:
- Bakteri dan partikel asing lainnya yang diserap dari usus dibuang
- Berbagai zat gizi yang diserap dari usus selanjutnya dipecah sehingga dapat digunakan
oleh tubuh.

Hati melakukan proses tersebut dengan kecepatan tinggi, setelah darah diperkaya dengan zat-zat
gizi, darah dialirkan ke dalam sirkulasi umum.
Hati menghasilkan sekitar separuh dari seluruh kolesterol dalam tubuh, sisanya berasal dari
makanan. Sekitar 80% kolesterol yang dihasilkan di hati digunakan untuk membuat empedu.
Hati juga menghasilkan empedu, yang disimpan di dalam kandung empedu.
Sebagai kelenjar, hati menghasilkan empedu yang mencapai ½ liter setiap hari. Empedu berasal
dari hemoglobin sel darah merah yang telah tua. Empedu merupakan cairan kehijauan dan terasa
pahit. Zat ini disimpan di dalam kantong empedu. Empedu mengandung kolestrol, garam
mineral, garam empedu, pigmen bilirubin, dan biliverdin. Empedu yang disekresikan berfungsi
untuk mencerna lemak, mengaktifkan lipase, membantu daya absorpsi lemak di usus, dan
mengubah zat yang tidak larut dalam air menjadi zat yang larut dalam air.
Sel-sel darah merah dirombak di dalam hati. Hemoglobin yang terkandung di dalamnya dipecah
menjadi zat besi, globin, dan heme. Zat besi dan globin didaur ulang, sedangkan heme dirombak
menjadi bilirubin dan biliverdin yang bewarna hijau kebiruan. Di dalam usus, zat empedu ini
mengalami oksidasi menjadi urobilin sehingga warna feses dan urin kekuningan. Apabila saluran
empedu di hati tersumbat, empedu masuk ke peredaran darah sehingga kulit penderita menjadi
kekuningan. Orang yang demikian dikatakan menderita penyakit kuning.
Sistem organ bayi anda menjadi terspesialisasi untuk fungsi tertentu. Khususnya hati. Fungsi hati
janin berbeda dengan orang dewasa. Enzim (kimiawi) dibuat oleh hati seorang dewasa, penting
untuk berbagai fungsi tubuh. Pada janin, enzim ini ada, tetapi kadarnya lebih rendah daripada
setelah lahir. Fungsi hati yang penting adalah pemecahan dan penanganan bilirubin. Bilirubin
dihasilkan dari perombakan sel darah merah. Masa hidup sel darah merah janin lebih pendek

daripada sel darah merah orang dewasa. Oleh karena itu, janin menghasilkan lebih banyak
bilirubin daripada orang dewasa.
Pada bayi baru lahir, enzim hati yang berfungsi sempurna sehingga banyak bilirubin tidak dapat
dikonjugasi dan bayi terlihat kuning. Namun, dengan bertambahnya umur bayi maka enzim hati
tersebut akan lebih baik fungsinya, bilirubin akan lebih banyak dikonjugasi, dan warna kuning
pada tubuh serta mata bayi berkurang, lalu menghilang. Proses ini memerlukan waktu sekitar
seminggu untuk bayi lahir dengan berat badan normal dan sekitar dua minggu untuk bayi lahir
dengan berat badan rendah. Biasanya peningkatan bilirubin pada keadaan ini jarang mencapai
kadar bilirubin yang berbahaya bagi bayi. Pada derajat tertentu, bilirubin ini akan bersifat toksik
dan merusak jaringan tubuh. Toksisitas ini terutama ditemukan pada bilirubin indirek yang
bersifat sukar larut dalam air tapi mudah larut dalam lemak. Sifat ini memungkinkan terjadinya
efek patologik pada sel otak apabila bilirubin tadi dapat menembus sawar darah otak. Kelainan
yang terjadi pada otak ini disebut kernikterus atau ensefalopati biliaris. Pada umumnya dianggap
bahwa kelainan pada susunan saraf pusat tersebut mungkin akan timbul apabila kadar bilirubin
indirek lebih dari 20 mg/dl. Mudah tidaknya bilirubin melalui sawar darah otak ternyata tidak
hanya tergantung dari tingginya kadar bilirubin tetapi tergantung pula pada keadaan neonatus
sendiri. Bilirubin indirek akan mudah melalui sawar daerah otak apabila pada bayi terdapat
keadaan imaturitas, berat lahir rendah, hipoksia, hiperkarbia, hipoglikemia, dan kelainan susunan
saraf pusat yang terjadi karena trauma atau infeksi.
KANDUNG EMPEDU & SALURAN EMPEDU
Empedu mengalir dari hati melalui duktus hepatikus kiri dan kanan, yang selanjutnya bergabung
membentuk duktus hepatikus umum.
Saluran ini kemudian bergabung dengan sebuah saluran yang berasal dari kandung empedu
(duktus sistikus) untuk membentuk saluran empedu umum. Duktus pankreatikus bergabung
dengan saluran empedu umum dan masuk ke dalam duodenum.
Sebelum makan, garam-garam empedu menumpuk di dalam kandung empedu dan hanya sedikit
empedu yang mengalir dari hati.

Makanan di dalam duodenum memicu serangkaian sinyal hormonal dan sinyal saraf sehingga
kandung empedu berkontraksi. Sebagai akibatnya, empedu mengalir ke dalam duodenum dan
bercampur dengan makanan.
Empedu memiliki 2 fungsi penting:
- Membantu pencernaan dan penyerapan lemak
- Berperan dalam pembuangan limbah tertentu dari tubuh, terutama hemoglobin yang
berasal dari penghancuran sel darah merah dan kelebihan kolesterol.
Secara spesifik empedu berperan dalam berbagai proses berikut:
- Garam empedu meningkatkan kelarutan kolesterol, lemak dan vitamin yang larut dalam
lemak untuk membantu proses penyerapan
- Garam empedu merangsang pelepasan air oleh usus besar untuk membantu
menggerakkan isinya
- Bilirubin (pigmen utama dari empedu) dibuang ke dalam empedu sebagai limbah dari sel
darah merah yang dihancurkan
- Obat dan limbah lainnya dibuang dalam empedu dan selanjutnya dibuang dari tubuh
- Berbagai protein yang berperan dalam fungsi empedu dibuang di dalam empedu.
Garam empedu kembali diserap ke dalam usus halus, disuling oleh hati dan dialirkan kembali ke
dalam empedu. Sirkulasi ini dikenal sebagai sirkulasi enterohepatik.
Seluruh garam empedu di dalam tubuh mengalami sirkulasi sebanyak 10-12 kali/hari. Dalam
setiap sirkulasi, sejumlah kecil garam empedu masuk ke dalam usus besar (kolon). Di dalam
kolon, bakteri memecah garam empedu menjadi berbagai unsur pokok. Beberapa dari unsur
pokok ini diserap kembali dan sisanya dibuang bersama tinja.
USUS BESAR

Usus besar terdiri dari:
- Kolon asendens (kanan)
- Kolon transversum
- Kolon desendens (kiri)
- Kolon sigmoid (berhubungan dengan rektum).
Apendiks (usus buntu) merupakan suatu tonjolan kecil berbentuk seperti tabung, yang terletak di
kolon asendens, pada perbatasan kolon asendens dengan usus halus.
Usus besar menghasilkan lendir dan berfungsi menyerap air dan elektrolit dari tinja. Ketika
mencapai usus besar, isi usus berbentuk cairan, tetapi ketika mencapai rektum bentuknya
menjadi padat.
Banyaknya bakteri yang terdapat di dalam usus besar berfungsi mencerna beberapa bahan dan
membantu penyerapan zat-zat gizi.
Bakteri di dalam usus besar juga berfungsi membuat zat-zat penting, seperti vitamin K. Bakteri
ini penting untuk fungsi normal dari usus. Beberapa penyakit serta antibiotik bisa menyebabkan
gangguan pada bakteri-bakteri di dalam usus besar. Akibatnya terjadi iritasi yang bisa
menyebabkan dikeluarkannya lendir dan air, dan terjadilah diare.

REKTUM & ANUS
Rektum adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar (setelah kolon sigmoid) dan
berakhir di anus.
Biasanya rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolon
desendens. Jika kolon desendens penuh dan tinja masuk ke dalam rektum, maka timbul
keinginan untuk buang air besar.Orang dewasa dan anak yang lebih tua bisa menahan keinginan
ini, tetapi bayi dan anak yang lebih muda mengalami kekurangan dalam pengendalian otot yang
penting untuk menunda buang air besar.
Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan, dimana bahan limbah keluar dari tubuh.
Sebagian anus terbentuk dari permukaan tubuh (kulit) dan sebagian lainnya dari usus. Suatu
cincin berotot (sfingter ani) menjaga agar anus tetap tertutup.
2. KASUS PEMICU
Anak R, seorang perempuan usia 8 tahun karena sering BAB 5-6 kali sehari. Terutama
sejak 2 minggu terakhir. Hal itu disebabkan karena pasien tidak memliki biaya untuk
berobat. Hasil pemeriksaan fisik: BB: 20 kg, TB: 135 cm, rambut kusam dan kering, kulit
kering dan garis yang dalam. Klien tampak pendiam, mata sayu dan sembab, perutnya
buncit, kaki bengkak, teraba dingin, hepar teraba 1-2 cm, HB : 8,7, gula darah seawaktu:
52 gr, kalium : 3, magnesium: 1, selama dilakukan pengkajian klien selalu melihat ibunya
seperti mimik muka menangis. Menurut ibunya, klien sering cengeng, tidak mau bergaul
dan tidak punya keinginan apapun. Tiga bulan terakhir ia tidak sekolah karena kalau
berjalan ia mudah kelelahan dan sulit berkonsentrasi dikelas. Klien tinggal dikawasan

padat penduduk. Luas rumah 42cm persegi. Ayahnya bekerja tidak tentu, tapi lebih sering
menjadi buruh di pasar. Ibunya tidak bekerja, hanya sekali-kali menerima cucian dari
orang lain.
A. DEFINISI
KEP (Kurang Energi Protein) adalah keadaan kurang gizi karena rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari sehingga tidak memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG). KEP juga dapat terjadi pada orang yang tidak mampu menyerap nutrisi penting atau mengkonversikannya menjadi energi penting untuk pembentukan jaringan sehat dan fungsi organ.
KEP adalah keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari sehingga tidak memenuhi Angka Kecukupan Gizi(AKG) dalam jangka waktu yang lama. Ciri fisik KEP adalah skor-z berat badan berada di bawah -2,0 standar baku normal.
(WHO) [1] mendefinisikan kekurangan gizi sebagai "ketidakseimbangan seluler antara pasokan nutrisi dan energi dan permintaan tubuh untuk menjamin pertumbuhan, pemeliharaan, dan fungsi-fungsi khusus."
Jenis KEP
KEP Primer sebagai hasil dari diet yang tidak memiliki sumber protein dan / atau energi yang tidak cukup.
KEP sekunder lebih umum di Amerika Serikat, di mana biasanya terjadi sebagai komplikasi AIDS, kanker, gagal ginjal kronis, penyakit radang usus, dan penyakit lainnya yang merusak kemampuan tubuh untuk menyerap atau menggunakan nutrisi atau untuk mengkompensasi kehilangan unsur hara. KEP dapat berkembang secara bertahap pada pasien yang memiliki penyakit kronis atau mengalami kronis semi-kelaparan. Ini mungkin muncul tiba-tiba pada pasien yang memiliki penyakit akut.
B. ETIOLOGI
Peranan diet.Menurut konsep, diet yang mengandung cukup energy tetapi kurang protein akan menyebabkan anak menjadi penderita kwasiorkhor, sedangkan diet kurang energy walaupun zat-zat gizi essensialnya seimbang akan menyebabkan anak menjadi marasmus. (solihin, 2000).
Peranan factor social.

- Pada pria dengan penghasilan kecil yang mempunyai anak banyak- Perceraian pada wanita yang mempunyai banyak anak
Peranan kepadatan pendudukKetika meningkatnya jumlah penduduk yang cepat tanpa di imbangi dengan bertambahnya persediaan bahan makanan yang memadai nerupakan sebab utama dari krisis pangan (world food conference).
Peranan infeksiInfeksi derajat apapun dapat memperburuk keadaan gizi. Ketika malnutrisi meskipun dalam keadaan ringan tetapi mempunyai pengaruh negative pada daya tahan tubuh terhadap infeksi.
Peranan kemiskinan
Klasifikasi
KEP ringan BB/U 70-80% baku median WHO-NHCS KEP sedang BB/U 60-70% baku median WHO-NHCS KEP berat BB/U < 60% baku median WHO-NHCS. KEP berat dibagi menjadi 3,
yaitu : Marasmus _ sindroma klinis akibat defisiensi kalori Kwashiorkor _ sindroma klinis akibat defisiensi protein berat Marasmik-kwashiorkor _ sindroma klinis akibat defisiensi protein dan kalori
1. secara langsung Anak kurang mendapatkan asupan gizi seimbang dalam waktu yang cukup lama Anak menderita penyakit infeksi, akibatnya asupan gizi tiak bisa dioptimalkan
oleh tubuh secra tidak langsung Tidak cukupnya persediaan pangan di rumah tangga Pola asupan kurang memadai Sanitasi/lingkungannya kurang baik Akses pelayanan kesehatan yang terbatas Rendahnya tingkat pendidikan dan pendapatan yang menyebabkan kemiskinan
Penyebab lainnya :
Perananan diet :diet mengandung cukup energi tapi kurang protein -> kwashiorkor
Kurang energi walaupun zat-zat gizi esensialnya seimbang akan menyebabkan anak menjadi marasmus (solihin,2000)
Peranan faktor sosial Peranan kepadatan penduduk Peranan infeksi
C. MANIFESTASI KLINIS

Untuk KEP ringan dan sedang, gejala klinis yang ditemukan hanya anak tampak kurus. Gejala klinis KEP berat/gizi buruk secara garis besar dapat dibedakan sebagai marasmus, kwashiorkor atau marasmic-kwashiorkor. Tanpa mengukur/melihat BB bila disertai edema yang bukan karena penyakit lain adalah KEP berat/Gizi buruk tipe kwasiorkor.
a. Kwashiorkor
- Edema, umumnya seluruh tubuh, terutama pada punggung kaki (dorsum pedis)- Wajah membulat dan sembab- Pandangan mata sayu- Rambut tipis, kemerahan seperti warna rambut jagung, mudah dicabut tanpa rasa
sakit, rontok- Perubahan status mental, apatis, dan rewel- Pembesaran hati- Otot mengecil (hipotrofi), lebih nyata bila diperiksa pada posisi berdiri atau duduk- Kelainan kulit berupa bercak merah muda yang meluas dan berubah warna
menjadi coklat kehitaman dan terkelupas (crazy pavement dermatosis)- Sering disertai : • penyakit infeksi, umumnya akut
anemia
diare.
b. Marasmus:- Tampak sangat kurus, tinggal tulang terbungkus kulit
- Wajah seperti orang tua
- Cengeng, rewel
- Kulit keriput, jaringan lemak subkutis sangat sedikit sampai tidak ada (baggy pant/pakai celana longgar)
- Perut cekung- Iga gambang- Sering disertai: - penyakit infeksi (umumnya kronis berulang)
- diare kronik atau konstipasi/susah buang air
c. Marasmik-Kwashiorkor:- Gambaran klinik merupakan campuran dari beberapa gejala klinik Kwashiorkor dan
Marasmus, dengan BB/U <60% baku median WHO-NCHS disertai edema yang tidak mencolok.
a) Kwashiokor :Tanda-tanda :1) Edema umumnya diseluruh tubuh terutama pada kaki2) Wajah membulat dan sembab3) Perubahan status mental : cengeng, rewel kadang apatis4) Anak sering menolak jenis makanan

5) Rambut berwarna kemerahan, kusam dan mudah dicabut6) Otot-otot mengecil, lebih nyata apabila diperiksa pada posisi berdiri dan duduk, anak lebih sering berbaring7) Sering disertai infeksi, anemia serta diare8) Gangguan kulit berupa bercak merah yang meluas dan berubah menjadi hitam terkelupas9) Pandangan mata anak tampak sayu
b) Marasmus Tanda-tanda :1) Anak tampak kurus, tinggal tulang terbungkus kulit2) Cengeng, rewel dan perut cekung3) Kulit keriput, jaringan lemak subkutis sangat sedikit sampai tidak ada4) Wajah seperti orang tua5) Sering disertai diare kronik / konstipasi serta penyakit kronik lainnya6) Tekanan darah, detak jantung dan pernafasan kurang
c) Marasmus – KwashiokorTanda-tandanya merupakan gabungan dari ke dua jenis KEP di atas (Moehji, 1992)
D. KLASIFIKASI
Klasifikasi KEP

Abbreviations: BMI, body mass index; HFA, height for age; MUAC, mid-upper arm circumference; SD, standard deviation; WFA, weight for age; WFH, weight for height; WHO, World Health Organization.
Gomez Classification: The child's weight is compared to that of a normal child (50th percentile) of the same age. It is useful for population screening and public health evaluations.
Percent of reference weight for age = [(patient weight) / (weight of normal child of same age)] * 100
Waterlow Classification: Chronic malnutrition results in stunting. Malnutrition also affects the child's body proportions eventually resulting in body wastage.
Percent weight for height = [(weight of patient) / (weight of a normal child of the same height)] * 100
Percent height for age = [(height of patient) / (height of a normal child of the same age)] * 100
KEP berat / gizi buruk secara klinis mempunyai 3 bentuk :o Marasmus _ sindroma klinis akibat defisiensi kalori o Kwashiorkor _ sindroma klinis akibat defisiensi protein berat o Marasmik-kwashiorkor _ sindroma klinis akibat defisiensi protein dan kalori
E. PEMERIKSAAN
PEMERIKSAAN FISIK
PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK
F. PENATALAKSANAAN
Pelayanan Gizi (Depkes RI, 1998)

Pelayanan gizi balita KEP pada dasarnya setiap balita yang berobat atau dirujuk ke
rumah sakit dilakukan pengukuran berat badan, tinggi badan dan LILA untuk menentukan
status gizinya, selain melihat tanda-tanda klinis dan laboratorium. Setelah diketahui balita
tersebut dalam tingkatan KEP yang berat khususnya kwashiorkor, maka balita tersebut
harus dirawat inap dan dilaksanakan sesuai pemenuhan kebutuhan nutrisinya. Selain hal
tersebut ada beberapa yang dapat kita lakukan yaitu:
1. Pengobatan Dan Pencegahan Kekurangan Cairan.
Tanda klinis yang sering dijumpai pada anak KEP berat dengan dehidrasi adalah ada
riwayat diare sebelumnya, anak sangat kehausan, mata cekung, nadi lemah, tangan
dan kaki teraba dingin, anak tidak buang air kecil dalam waktu yang cukup lama.
Tindakan yang dapat dilakukan:
a. Jika anak masih menyusui, teruskan ASI dan berikan setiap 1/2jam sekali tanpa
berhenti. Jika anak masih dapat minum, lakukan tindakan rehidrasi oral dengan
memberi minum anak 50 ml (3 sdm) setiap 30 menit dengan sendok. Cairan
rehidrasi oral khusus KEP disebut ReSoMal.
b. Jika tidak ada ReSoMal untuk anak dengan KEP berat dapat menggunakan oralit
yang diencerkan 2x. Jika anak tidak dapat minum, lakukan rehidrasi intravena
(infus) RL/Glukosa 5% dan NaCl dgn perbandingan 1:1.
2. Lakukan Pemulihan Gangguan Keseimbangan Elektrolit
Pada semua KEP Berat/gizi buruk terjadi gangguan keseimbangan elektrolit
diantaranya adalah kelebihan natrium (Na) tubuh (walaupun kadar Na plasma rendah,
dan juga defisiensi Kalium (K) dan Magnesium (Mg).
Ketidakmampuan elektrolit ini memicu terjadinya edema dan untuk pemulihan
keseimbangan elektrolit diperlukan waktu minimal 2 minggu. Berikan makanan tanpa
diberi garam/rendah garam, untuk rehidrasi, berikan cairan oralit 1 liter yang
diencerkan 2x (dengan penambahan 1 liter air) ditambah 4 gr kecil dan 50 gr gula atau
bila balita KEP bisa makan berikan bahan makanan yang banyak mengandung mineral
bentuk makanan lumat
3. Lakukan Pengobatan Dan Pencegahan Infeksi.

Pada KEP berat tanda yang umumnya menunjukkan adanya infeksi seperti
demam seringkali tidak tampak. Pada semua KEP berat secara rutin diberikan antibiotik
spektrum luar.
4. Pemberian Makanan, Balita KEP Berat.
Pemberian diet KEP berat dibagi 3 fase :
1. Fase Stabilisasi (1–2 hari)
Pada awal fase stabilisasi perlu pendekatan yang sangat hati-hati, karena keadaan
faali anak yang sangat lemah dan kapasitas homeostatik berkurang, Pemberian
makanan harus dimulai segera setelah anak dirawat dan dirancang sedemikian rupa
sehingga energi dan protein cukup untuk memenuhi metabolisme basal saja,
Formula khusus seperti formula WHO 75/modifikasi/modisko ½ yang dilanjutkan
dan jadual pemberian makanan harus disusun agar dapat mencapai prinsip tersebut
dengan persyaratan diet sbb: porsi kecil, sering, rendah serat dan rendah laktosa,
energi 100 kkal/kg/hari, protein 1–1,5 gr/kgbb/hari, cairan 130 ml/kg BB/hari (jika
ada edema berat 100 ml/kg bb/hari),bila anak mendapat ASI teruskan, dianjurkan
memberi formula WHO 75/pengganti/modisco ½ dengan gelas, bila anak terlalu
lemah berikan dengan sendok/pipet, Pemberian formula WHO
75/pengganti/modisco ½ atau pengganti dan jadual pemberian makanan harus
sesuai dengan kebutuhan anak.
2. Fase Transisi (minggu II)
a. Pemberian makanan pada fase transisi diberikan secara perlahan untuk
menghindari resiko gagal jantung, yang dapat terjadi bila anak
mengkonsumsi makanan dalam jumlah banyak secara mendadak.
b. Ganti formula khusus awal (energi 75 kal dan protein 0.9 – 1.0 gr/100 ml)
dengan formula khusus lanjutan (energi 100 kkal dan protein 2.9 gr/100
ml) dalam jangka waktu 48 jam . Modifikasi bubur/mknn keluarga dapat
digunakan asal kandungan energi dan protein sama

c. Naikkan dengan 10 ml setiap kali sampai hanya sedikit formula tersisa,
biasanya pada saat tercapai jumlah 30 ml/kg bb/kali pemberian (200 ml/kg
bb/hari).
3. Fase Rehabilitasi (Minggu III–VII)
a. Formula WHO-F 135/pengganti/modisco 1 ½ dengan jumlah tidak terbatas
dan sering.
b. Energi : 150–220 kkal/kg bb/hari.
c. Protein : 4–6 gr/kgbb/hari.
d. Bila anak masih mendapat ASI, teruskan ASI, ditambah dengan makanan
formula karena energi dan protein ASI tidak akan mencukupi untuk
tumbuh kejar.
e. Secara perlahan diperkenalkan makanan keluarga.
5. Lakukan Penanggulangan Kekurangan Zat Gizi Mikro
Semua pasien KEP berat mengalami kurang vitamin dan mineral, walaupun
anemia biasa terjadi, jangan tergesa-gesa memberikan preparat besi (Fe). Tunggu
sampai anak mau makan dan BB nya mulai naik (pada minggu II). Pemberian Fe pada
masa stabilisasi dapat memperburuk keadaan infeksinya . Berikan setiap hari :
a. Tambahan multivitamin lain
b. Bila BB mulai naik berikan zat besi dalam bentuk tablet besi folat/sirup besi
c. Bila anak diduga menderita cacingan berikan pirantel pamoat dosis tunggal.
d. Vitamin A oral 1 kali.
e. Dosis tambahan disesuaikan dgn baku pedoman pemberian kapsul vitamin A
6. Berikan Stimulasi Dan Dukungan Emosional
Pada KEP berat terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku,
karenanya diberikan : kasih sayang, ciptakan lingkungan menyenangkan,.lakukan terapi
bermain terstruktur 15-330 menit/hari, rencanakan aktifitas fisik setelah sembuh,
tingkatkan keterlibatan ibu (memberi makan, memandikan, bermain)
7. Persiapan Untuk Tindak Lanjut Di Rumah

Bila BB anak sudah berada di garis warna kuning anak dapat dirawat di rumah dan
dipantau oleh tenaga kesehatan puskesmas di desa.
G. LEGAL ETIK
1. Autonomy (Otonomi)
Klien bisa menerima/menolak pelayanan kesehatan apa yang akan dilakukan
padanya.
2. Beneficience (berbuat baik)
Perawat sebagai bagian tim pelayanan kesehatan harus menjaga sikap dan perilaku
yang baik juga melakukan intervensi yang baik untuk klien.
3. Justice (keadilan)
Perawat tidak boleh membeda-bedakan klien dalam pelayanan kesehatan (praktiknya)
sehingga perawat harus adil.
4. Non-Malifecience (Tidak merugikan)
Perawat tidak dengan sengaja melakukan tindakan yang merugikan diri klien
misalnya dengan tidak sengaja pola asupan nutrisi.
5. Veracity (kejujuran)
Perawat harus jujur kepada klien tentang penyakitnya.
6. Fideity (Menepati janji)
Perawat mempertahankan prinsifnya untuk tetap patuh pada kode etik yang
mengatakan bahwa dirinya akan selalu meningkatkan pelayanan kesehatan, mencegah
penyakit, pemulihan, dan meminimalkan penderitaan klien.
H. PATOFISIOLOGI
BAB III
ASUHAN KEPERAWATAN
1. Pengkajian keperawatan

Biografi Klien
Nama : An. R
Usia : 8 tahun
Sex : Perempuan
Agama : -
Pekerjaan : sudah tidak sekolah
KU : Klien mengeluh sering BAB 5-6 kali/sehari sejak 2 minggu terakhir
Riwayat Kesehatan Sekarang
BAB sering 5-6 kali/hari, mata sayu dan sembab, keleahan, cengeng,
Riwayat Kesehatan Masa Lalu
Kelelahan kalau berjalan, sulit berkonsentrasi sejak 3 bulan yang lalu
Riwayat Kesehatan Keluarga
Tidak teridentifikasi.
Riwayat Lingkungan
Kondisi rumah : tinggal dikawasan padat penduduk
Pekerjaaan orang tua : ayah sebagai buruh di pasar
Ibu ibu rumah tangga terkadang menjadi buruh cuci
Pemeriksaan Fisik
TTV : BB = 20 kg TB = 15 cm
Kepala : rambut kusam dan kering, mata sayu dan sembab, mimic muka seperti menangis
Kulit : kulit keering dan garis dalam dan suhu akral dingin
Abdomen : perut buncit dan hepar teraba 1-2 cm
Ekstremitas : kaki bengkak teraba dingin
Hasil Laboratoriun
Hb : 8,7
Gudarah sewaktu : 52gr
Kalium : 3

Magnesium : 1
2. Analisa data
No. Data Menyimpang Etiologi Diagnosa
1. DO: - acetabular panggul klien
tampak rusak
DS: - Klien mengeluh nyeri
pada sendi panggul samapai
tidak bisa digerakkan dengan
skala 7
Trauma panggul
rusaknya kartilago
artikular
terjadi nekrosis
sendi
pelepasan mediator
kimia
Nyeri
Kekurang volume cairan tubuh
2. DS: pasien berkata ia sudah
tidak bisa bekerja lagi karena
panggulnya tidak bisa
digerakkan
DO: -
trauma panggul
rusaknya kartilago
artikular
terjadi nekrosis
sendi
nyeri
kaki sulit digerakan
sulit melakukan
aktivitas
gangguan mobilitas
fisik
Gg. Mobilitas fisik

3. DS : pasien mengatakan takut
operasi
DO : -
Trauma panggul
Rusaknya karilao
artikular
Terjadi nekrosis
sendi
Perlu penggantian
sendi
Kurang
pengetahuan / salah
interpretasi
Pengalaman masa
lalu
Ansietas
Ansietas
3. Asuhan Keperawatan
No Diagnosa Tujuan Intervensi Rasional
1. Kekurangan volume
cairan tubuh
berhubungan
dengan
peningkatan
asupan peroral
dan peningkatan
kehilangan akibat
diare.
Kx akan menunjukkan keadaan hidrasi
yang adekuat menjadi 2-3
TTV normal
Asupan cairan sesuai
kebutuhan
ditambah defisiy
Lakukan / observasi
pemberian cairan perinfus /
sande / oral sesuai dengan
program rehidrasi
b. Jelaskan kepada keluarga
tentang upaya rehidrasi dan
peran keluarga dalam
pelaksanaan terapi rehidrasi
c. Kaji perkembangan
a. Upaya rehidrasi perlu
dilakukan untuk
mengatasi masalah
kekurangan volume cairan
b. Meningkatkan
pemahaman keluarga
tentang upaya rehidrasi
dan peran keluarga dalam
pelaksanaan terapi

yang terjadi
tidak ada tanda /
gejala dehidrasi
(TTV dalam
batas normal,
frekuensi
defekasi 1 x
24 jam dengan
kosistensi
padat / semi
padat).
keadaan dehidrasi Kx
d. Hitung balans cairan
rehidrasi
c. Menilai perkembangan
masalah Kx
d. Penting untuk
menetapkan dehidrasi
selanjutnya
2. Gangguan
pertumbuhan dan
perkembangan
berhububungan
dengan asupan
protein dan kalori
yang tidak
adekuat.
Tujuan : Kx
akan mencapai
pertumbuhan
dan
perkembangan
standart usia
KH :
- Pertumbuhan
fisik (ukuran
antropometri)
sesuai standart
usia
- Perkembangan / bahasa / kognitif dan personal / sosial sesuai standart usia
a. Lakukan pemberian
makanan / minuman sesuai
program terapi diet
pemilihan
b. Lakukan pengukuran
antropometri secara berkala
c. Lakukan stimulasi tingkat
perkembangan sesuai
dengan usia Kx
d. Ajarkan kepada orang tua
tentang standart
pertumbuhan fisik dan
tugas-tugas perkembangan
sesuai umur.
a. Diet khusus untuk
pemeliharaan mal nutrisi
diprogramkan secara
bertahap sesuai dengan
kebutuhan anak dan
kemampuan toloransi
sistem pencernaan
b. Menilai perkembangan
masalah Kx
c. Stimulasi di perlukan untuk
mengejar keterlambatan
perkembangan anak dalam
aspek motorik, bahasa dan
personal / sosial
d. Meningkatkan pengetahuan
keluarga tentang
keterlambatan pertumbuhan
dan perkembangan anak.
3.

BAB IV
PENUTUP
SIMPULAN
\
DAFTAR PUSTAKA
- Potter & Perry .2005. Buku Ajaringan Fundamental Keperawatan: Konsep, Proses,dan
Praktik. Edisi 4, Vol. 2. Alih Bahasa: Renata Komalasari. Jakarta: EGC.
- Suratun,H. 2008. Klien Gangguan Sistem Muskuloskeletal. Jakarta : EGC
- Carpenito, Lynda Juall. 1995. Diagnosa Keperawatan Aplikasi Pada Praktek Klinik.
Edisi 6, Jakarta :EGC.
- Corwin,E. 2009. Buku Saku Patofisiologi. Jakarta :EGC.
- Doenges, M. G. 2000. Rencana Asuhan Keperawatan, Edisi 3. Jakarta : EGC
- Ganong F. William. 1998. Buku Ajaringan Fisiologi Kedokteran Edisi 17. Jakarta : EGC
- Price, Silvia A. 2005. Patofisiologi : Konsep Klinis Proses- Proses Penyakit. Edisi 6.
Jakarta :EGC
- http://dokterpatahtulang.com/operasi-bedah-tulang-2/tindakan-operasi-ganti-sendi/
- scribd.com /doc/91321776/total-jonit-replacement

- Smeltzer., S. 2012. Keperawatan Medikal Bedah. Jakarta : EGC
- Baziad, Ali, Djamaloeddin, Erdjan Akbar, Handaya dkk. Anatomi Panggul dan Isinya
dan Haid dan Siklusnya.
- Putz,Reinhard dan Reinhard Pabst.Ekstremitas Bawah , Pelvis.Liliana Sugiarto.Sobotta:
Atlas Anatomi Manusia edisi 22, jilid 2.